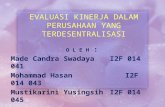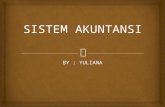9 BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasi Akuntansi ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of 9 BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasi Akuntansi ...
9
BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1 Sistem Informasi Akuntansi
2.1.1 Pengertian Sistem Informasi
Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur dan kombinasi dari
pengguna, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber-sumber
data yang mengumpulkan, memproses dan mendistribusikan informasi.
Penjelasan di atas mengacu kepada pendapat Laudon dan Laudon (2009, p.8),
sistem informasi secara teknikal dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen
yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan
menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan mengendalikan
organisasi.
Dan juga berdasarkan pendapat O’Brien (2005, p.5), sistem informasi dapat
merupakan kombinasi dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan
komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan
informasi dalam sebuah organisasi.
2.1.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
Sistem informasi akuntansi adalah salah satu subsistem dari sistem informasi
manajemen yang berfungsi untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengolah
data-data dalam proses transaksi akuntansi yang rutin untuk menghasilkan informasi
akuntansi dan keuangan yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.
10
Penjelasan di atas mengacu kepada pendapat Jones dan Rama (2006,p.5), Sistem
informasi akuntansi adalah sebuah subsistem dari sistem informasi manajemen yang
menyediakan informasi akuntansi dan keuangan, bersama informasi lainnya yang
diperoleh dalam proses transaksi akuntansi yang rutin.
Dan juga berdasarkan pendapat Romney dan Steinbart (2008, p.6), Sistem
informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan
memproses data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan.
Menurut Hall (2009, p65), terdapat tiga siklus dalam siklus transaksi antara lain :
1. Siklus Pengeluaran (p65)
Aktivitas bisnis di mulai dengan pemerolehan bahan baku, properti, dan tenaga kerja
melalui pertukaran dengan kas – siklus pengeluaran. Subsistem-subsistem utama
dari siklus pengeluaran antara lain:
a. Sistem pembelian/utang
b. Sistem pengeluaran kas
c. Sistem penggajian
d. Sistem aktiva tetap
2. Siklus Pendapatan (p67)
Perusahaan menjual barang jadi ke pelanggan melalui siklus pendapatan,yang
melibatkan pemrosesan penjualan tunai, penjualan kredit, dan penerimaan kas
setelah penjualan kredit.
3. Siklus Konversi (p66)
Siklus konversi terdiri atas dua subsistem utama : sistem produksi dan sistem
akuntansi biaya. Sistem produksi melibatkan perencanaan, penjadwalan dan
11
pengendalian produk fisik melalui proses produksi. Hal ini termasuk menetapkan
kebutuhan bahan baku, otorisasi kerja yang harus dilakukan dan pelepasan bahan
baku ke produksi , serta mengarahkan pergerakan barang dalam proses melalui
berbagai tahap proses-proses. Sistem akuntansi biaya memantau arus informasi
biaya yang berkaitan dengan dengan produksi. Informasi yang dihasilkan oleh
sistem ini digunakan untuk penilaian persediaan, penganggaran, pengendalian biaya,
pelaporan kinerja, dan keputusan manajemen seperti keputusan “membuat atau
membeli”
2.1.3 Manfaat Sistem Informasi Akuntansi
Kegunaan Sistem Informasi Akuntansi menurut Jones dan Rama (2006,p.6),
antara lain :
a. Menghasilkan External Report
Bisnis menggunakan sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan
laporan-laporan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi investor,
kreditor, petugas pajak, agen pengatur dan lain-lain.
b. Mendukung Aktivitas Rutin
Manajer membutuhkan sistem informasi akuntansi untuk menangani aktivitas
operasional yang rutin dalam siklus operasi perusahaan. Contohnya antara
lain : melayani pemesanan pelanggan, pengiriman barang dan jasa, penagihan
kepada pelanggan, dan penerimaan kas.
12
c. Pengambilan Keputusan
Informasi juga dibutuhkan untuk pengambilan keputusan tidak rutin pada
semua level dari organisasi. Contohnya antara lain : mengetahui barang yang
penjualannya baik dan pelanggan yang paling banyak melakukan pembelian.
d. Perencanaan dan Pengendalian
Sebuah sistem informasi dibutuhkan untuk aktivitas perencanaan dan
pengendalian
e. Implementasi Pengendalian Internal
Pengendalian internal meliputi kebijakan, prosedur dan sistem informasi
yang digunakan untuk melindungi harta (asset) perusahaan dari kerugian atau
pencurian dan untuk memelihara keakuratan data keuangan
2.2 Sistem Informasi Akuntansi Persediaan
2.2.1 Pengertian Persediaan
Persediaan merupakan seluruh barang yang dimiliki oleh perusahaan dengan
maksud untuk dijual dalam suatu periode operasi normal, termasuk juga bahan baku
(barang yang digunakan untuk proses produksi), barang dalam proses (barang yang
masih dalam proses produksi), serta produk jadi (barang yang siap untuk dijual)
sehingga dapat memenuhi permintaan para pelanggan.
Berdasarkan pendapat Warren et al. (2005, p344), persediaan digunakan untuk
mengindikasikan (1) barang dagangan yang disimpan untuk dijual selama dalam operasi
bisnis yang normal (2) bahan-bahan dalam proses produksi atau yang disimpan untuk
produksi.
13
Russel dan Taylor (2006, p529) mendefinisikan persediaan merupakan sebuah
stok dari item-item yang disimpan oleh suatu organisasi untuk memenuhi permintaan
para pelanggan internal atau eksternal.
2.2.2 Sistem Persediaan
Menurut Weigandt et al. (2005, p220) terdapat dua sistem persediaan, yaitu :
1. Sistem Persediaan Periodik
Dalam sistem periodik, perusahaan tidak selalu mencatat yang terjadi pada
persediaan yang dimilikinya. Akibatnya, pada akhir periode, perusahaan harus
melakukan perhitungan fisik untuk mengetahui jumlah persediaan yang dimilki
pada saat itu. Jumlah persediaan tersebut akan dikalikan dengan unit biaya untuk
mendapatkan harga pokok persediaan pada akhir periode. Angka ini akan masuk
ke dalam neraca. Angka ini juga digunakan untuk menghitung harga pokok
penjualan. Sistem periodic disebut juga sistem fisik, karena sistem ini tergantung
pada hasil persediaan secara fisik pada akhir periode. Sistem ini biasanya
digunakan untuk mencatat persediaan yang nilainya tidak tinggi, karena dari segi
biaya, tidak begitu menguntungkan untuk mempunyai catatan untuk setiap dari
barang yang rendah nilainya.
2. Sistem Persediaan Perpetual
Dalam sistem perpetual, perusahaan akan mencatat setiap yang terjadi pada
persediaan barangnya. Jadi akun persediaan akan selalu menunjukkan nilai
persediaan setiap saat. Pencatatan secara perpetual berguna untuk menyediakan
laporan bulanan, kuartalan, ataupun laporan interim, dimana perusahaan dapat
14
lansung menentukan jumlah dan harga pokok persediaan yang dimilikinya tanpa
harus menghitung persediaan fisik terlebih dahulu. Sistem persediaan perpetual
juga memberikan tingkat pengendalian terhadap persediaan yang lebih akurat
dibandingkan sistem periodik karena informasi mengenai persediaan dalam
sistem perpetual selalu mencerminkan keadaan persediaan saat ini.
2.2.3 Metode Penilaian Persediaan
Menurut pendapat Weigandt et al. (2005, p237), terdapat tiga metode penilaian
terhadap persediaan, yaitu :
1. Specific Identification Method
Metode ini menelusuri arus fisik aktual dari barang. Masing-masing jenis
persediaan ditandai, diberi label, ataupun diberi kode sesuai dengan spesifik
biaya per unitnya. Pada akhir periode, biaya spesifik dari persediaan yang masih
menjadi persediaan merupakan biaya total dari persediaan akhir.
2. First-in, First-Out method (FIFO)
First-in, First-Out method (FIFO) adalah metode penilaian persediaan yang
menganggap barang yang pertama kali masuk diasumsikan keluar pertama kali
pula. Pada umumnya perusahaan menggunakan metode ini, sebab metode ini
perhitungannya sangat sederhana baik sistem fisik maupun sistem perpetual akan
menghasilkan penilaian persediaan yang sama. Dengan metode FIFO, harga
pokok barang yang lebih dulu dibeli merupakan biaya yang pertama kali diakui
sebagai harga pokok penjualan.
15
3. Last-in, First-out method (LIFO)
Last-in, First-out method (LIFO) adalah metode penilaian persediaan yang
terakhir masuk diasumsikan akan keluar atau ditetapkan dalam menghitung harga
pokok penjualan. Metode ini memiliki konsep yang cukup sederhana namun sulit
dilaksanakan. Pengaruh penggunaan metode LIFO terhadap penentuan laba
bersih usaha, jika harga cenderung naik maka laba perusahaan terlalu kecil atau
sebaliknya.
4. Average method (Metode rata-rata)
Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang tersedia untuk dijual memiliki
biaya per unit yang sama (rata-rata). Besar kecilnya nilai persediaan yang masih
ada dan harga pokok barang yang dijual, dipengaruhi oleh metode yang dipakai
dalam metode rata-rata adalah (1) sistem fisik yang dibagi menjadi metode rata-
rata sederhana dan metode rata-rata tertimbang; (2) sistem perpetual (metode
rata-rata bergerak).
2.2.4 Metode Pengendalian Persediaan
Metode pengendalian persediaan terdiri dari kuantitas pemesanan ekonomis, titik
pemesanan kembali, serta persediaan/stok pengaman sebagaimana diuraikan berikut:
1. Kuantitas Pemesanan Ekonomis (Economic Order Quantity atau EOQ)
Pengendalian persediaan bertujuan untuk meminimalkan total biaya
persediaan sehingga suatu keputusan penting yang perlu dibuat merupakan
ukuran setiap kuantitas pemesanan pembelian, yaitu economic order quantity
(EOQ). Kuantitas pemesanan pembelian harus menyeimbangkan dua sistem
16
biaya, yaitu total biaya penyimpanan (carrying cost) dan total biaya
pemesanan (ordering cost). Setelah EOQ dikalkulasi, waktu pemesanan
harus diputuskan, yaitu ROP harus ditentukan.
2. Titik Pemesanan Kembali (Re-order point atau ROP)
Suatu ROP merupakan tingkat persediaan ketika diperlukan sekali untuk
memesan atau menghasilkan items tambahan untuk menghindari kondisi
kehabisan stok persediaan. Pengembangan ROP memerlukan suatu analisis
permintaan produk, biaya pemasangan (setup) produksi atau pemesanan, lead
time produksi atau pemasok, biaya penyimpanan (holding) persediaan, dan
biaya yang berhubungan dengan kondisi kehabisan stok persediaan, seperti
kehilangan penjualan (lost sales) atau penggunaan yang tidak efisien dari
fasilitas-fasilitas produksi.
Jika lead time pemesanan tingkat penggunaan persediaan diketahui,
penentuan ROP dapat langsung diperoleh. Lead time merupakan waktu di
antara penempatan pesanan dan penerimaan barang. Tingkat penggunaan
persediaan (inventory usage rate) merupakan kuantitas barang yang
digunakan selama periode waktu. ROP seharusnya terjadi ketika tingkat
persediaan mencapai jumlah unit yang akan dikonsumsi selama lead time,
dengan rumus sebagai berikut :
Reorder point (ROP) = lead time x average inventory usage rate
ROP terjadi ketika persediaan mencapai sebelum nol, kemudian perusahaan
melakukan pemesanan kembali, dan dengan seketika barang yang dipesan
diterima. Perhitungan ROP menggunakan rumus sebagai berikut (persamaan
17
di bawah ini mengasumsikan bahwa permintaan selama lead time dan lead
time sendiri adalah konstan):
ROP = d x L
Keterangan:
ROP = titik pemesanan ulang
d = Permintaan per hari
L = lead time untuk pemesanan baru atau waktu pengiriman (dalam
hari)
Permintaan per hari, d, dapat dicari dengan membagi permintaan tahunan, D,
dengan jumlah hari kerja per tahun sebagai berikut :
d = D
jumlah hari kerja per tahun
2.3 Sistem Pengendalian Internal
2.3.1 Definisi Sistem Pengendalian Internal
Pengendalian Internal adalah suatu sistem pengendalian yang berupa aturan,
kebijakan, prosedur dan sistem informasi yang dihasilkan juga akurat dan dapat
diandalkan, tingkat efektivitas dan efisiensi operasional, serta memastikan bahwa segala
kebijakan dan peraturan yang ada dapat dipatuhi sebagaimana mestinya.
Menurut Gelinas dan Dull (2008, p.216), yang terdapat dalam Committee of
Sponsoring Organization (COSO), pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu
proses yang dipengaruhi oleh suatu dewan direksi, manajemen, dan pihak personal
lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan jaminan atau keyakinan
18
yang layak atau memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan denagn kategori sebagai
berikut: efektivitas dan efisiensi operasi, kehandalan laporan keuangan, dan kesesuaian
dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
2.3.2 Komponen-Komponen Pengendalian Internal
Menurut Jones dan Rama (2006, p.105), komponen-komponen yang
berhubungan dengan pengendalian internal terdiri dari lima komponen, yaitu:
1. Lingkungan Pengendalian
Berhubungan dengan beberapa faktor yang disusun oleh organisasi untuk
mengendalikan kesadaran para karyawannya. Faktor tersebut berhubungan
dengan integritas, nilai etika, filosofi manajemen dan gaya operasional.
Termasuk di dalamnya cara manajemen menetapkan otoritas dan tanggung
jawab, mengatur, dan mengembangkan sumber daya manusia serta perhatian dan
petunjuk Dewan Direktur.
2. Penilaian Resiko
Merupakan proses identifikasi dan analisis terhadap resiko yang dapat
menghambat pencapaian tujuan pengendalian internal.
3. Aktivitas Pengendalian
Merupakan kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi untuk
menangani resiko-resiko yang mungkin dan telah ada. Aktivitas pengendalian
mencakup:
• Performance Review, kegiatan yang berhubungan dengan analisis terhadap
kinerja, misalnya dengan membandingkan hasil yang didapat dengan
anggaran, standar perhitungan, dan data pada periode sebelumnya.
19
• Segregation of Duties, terdiri dari penetapan tanggung jawab untuk
mengotorisasi transaksi, melakukan transaksi, mencatat transaksi, dan
menjaga aset yang dilakukan oleh karyawan yang berbeda.
• Application Control, yang berhubungan dengan aplikasi sistem informasi
akuntansi.
• General control, berhubungan dengan pengawasan yang lebih luas yang
berhubungan dengan berbagai aplikasi.
4. Informasi dan Komunikasi
Sistem informasi perusahaan adalah kumpulan dari prosedur (baik otomatis
maupun manual) dan pencatatan dalam memulai, mencatat, memproses, dan
melaporkan kejadian atas proses-proses yang terjadi dalam organisasi. Dan
komunikasi berhubungan dengan menyediakan pemahaman atas peraturan dan
tanggung jawab tertentu.
5. Pengawasan
Manajemen harus mengawasi pengendalian internal untuk memastikan bahwa
pengendalian internal organisasi berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.
2.4 Perencanaan Produksi
Menurut Assauri (2008, h.181) perencanaan produksi adalah perencanaan dan
pengorganisasian sebelumnya mengenai orang-orang, bahan-bahan, mesin-mesin dan
peralatan lain serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang-barang pada
suatu periode tertentu di masa depan sesuai dengan yang diperkirakan atau diramalkan.
20
Barang yang direncanakan akan diproduksi pada suatu periode di masa depan harus
memenuhi beberapa syarat, yaitu :
a. barang tersebut harus dapat diproduksi atau dibuat pada waktu itu
b. barang tersebut harus dapat dikerjakan dengan atau oleh pabrik ini,
c. barang tersebut harus sesuai dengan atau dapat memenuhi atau dicocokan
dengan keinginan pembeli sesuai dengan ramalan baik mengenai harga,
kuantitas,kualitas dan waktu yang dibutuhkan
Tujuan perencanaan produksi adalah :
a. untuk mencapai tingkat /level keuntungan (profit) yang tertentu. Misalnya
berapa hasil (output) yang diproduksi supaya dapat dicapai tingkat/level
profit yang diinginkan dan dan tingkat persentase tertentu dari keuntungan
(profit) setahun terhadap penjualan (sales) yang diinginkan
b. untuk menguasai pasar tertentu, sehingga hasil atau output perusahaan ini
tetap mempunyai pangsa pasar (market share) tertentu
c. untuk mengusahakan supaya perusahaaan pabrik ini dapat bekerja pada
tingkat efisiensi tertentu.
d. untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan
kerja yang sudah ada tetap pada tingkatnya dan berkembang.
e. untuk menggunakan sebaik-baiknya (efisien) fasilitas yang sudah ada pada
perusahaan yang bersangkutan.
21
2.5 Biaya Pada Perusahaan Manufaktur
2.5.1 Pengertian Biaya
Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan tindakan ekonomis adalah suatu
pengorbanan nilai dari faktor-faktor produksi. Biaya merupakan pengorbanan sumber
daya ekonomi dalam bentuk kas atau aktiva lain (nonkas) yang dikeluarkan untuk
menghasilkan dan memperoleh barang dan jasa yang diharapkan memberikan manfaat
bagi perusahaan di masa yang akan datang.
Biaya menurut Hansen dan Mowen (2009, h.47) adalah asset kas atau nonkas
yang dikorbankan untuk barang dan jasa yang diharapkan keuntungan bagi perusahaan
pada masa sekarang atau yang akan datang.
Menurut Witjaksono (2006,h.6) terdapat beberapa definisi biaya antara lain
adalah :
1. Cost adalah pengorbanan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2. Sebagian akuntan mendefinisikan biaya sebagai satuan moneter atas
pengorbanan barang dan jasa untuk memperoleh manfaat di masa kini atau
masa yang akan datang
2.5.2 Pengertian Akuntansi Biaya
Akuntansi biaya adalah akuntansi yang menyediakan informasi biaya untuk
membantu manajemen agar dapat mengelola biaya secara efektif dan efisien
Menurut Witjaksono (2006, h.1) akuntansi biaya dapat didefinisikan sebagai
“ilmu dan seni mencatat, mengakumulasikan, mengukur serta menyajikan informasi
berkenaan dengan biaya dan beban”
22
Horngren dan Datar (2005, h.3) menyatakan, Akuntansi Biaya menyediakan
informasi yang dibutuhkan untuk akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan.
Akuntansi biaya mengukur dan melaporkan setiap informasi keuangan dan nonkeuangan
yang terkait dengan daya perolehan atau pemanfaatan sumber daya dalam suatu
organisasi..
2.5.3 Klasifikasi Biaya Pada Perusahaan Manufaktur
Biaya dapat dikelompokkan dengan berbagai macam cara. Pada umumnya
klasifikasi biaya ditentukan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dari penggolongan
tersebut
Menurut Hansen dan Mowen (2009,h.56), biaya dikelompokkan dalam dua
kategori fungsional utama :
1. Biaya produksi
Biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan
penyediaan jasa. Biaya produksi dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai :
a. Bahan Langsung
Bahan langsung adalah bahan yang dapat ditelusuri secara langsung pada
barang atau jasa yang sedang diproduksi. Biaya bahan ini dapat langsung
dibebankan pada produk karena pengamatan secara fisik dapat digunakan
untuk mengukur kuantitas yang dikonsumsi setiap produk.
b. Tenaga Kerja Langsung
Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara
langsung pada barang atau jasa yang sedang diproduksi. Karyawan yang
23
mengubah bahan baku menjadi produk atau menyediakan jasa kepada
pelanggan diklasifikasikan sebagai tenaga kerja langsung.
c. Overhead
Semua biaya produksi – selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung
– dikelompokkan dalam satu kategori yang disebut overhead. Pada
perusahaan manufaktur, overhead juga dikenal sebagai beban pabrik
(Factory Overhead) atau overhead manufaktur (Manufacturing
Overhead).
d. Biaya Utama dan Konversi
Kombinasi dari berbagai biaya produksi mengarah pada konsep biaya
konversi dan biaya utama. Biaya utama (Prime Cost) adalah jumlah dari
biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya konversi
(Conversion Cost) adalah jumlah dari biaya tenaga kerja langsung dan
biaya overhead. Untuk perusahaan manufaktur, biaya koversi bisa
diinterpretasikan sebagai biaya untuk mengonversi bahan baku menjadi
produk akhir.
2. Biaya nonproduksi
Biaya nonproduksi adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi desain,
pengembangan pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi
umum. Biaya nonproduksi sering dibagi menjadi dua kategori umum yaitu :
a. Biaya Penjualan
Biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan, dan
melayani produk atau jasa merupakan biaya pemasaran (penjualan).
24
Biaya ini sering disebut sebagai biaya mendapatkan pesanan (order
getting cost) dan biaya memenuhi pesanan (order filling cost). Contoh
biaya mendapatkan pesanan adalah gaji dan komisi tenaga penjual dan
iklan. Contoh biaya memenuhi pesanan adalah pergudangan, pengiriman,
dan layanan pelanggan.
b. Biaya administrasi
Seluruh biaya yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan dan
administrasi umum pada organisasi yang tidak dapat dibebankan pada
pemasaran ataupun produksi, dikelompokkan sebagai biaya administrasi.
Administrasi umum bertanggung jawab dalam memastikan bahwa
berbagai aktivitas organisasi terintegrasi secara tepat sehingga misi
perusahaan secara keseluruhan dapat terealisasi. Contoh biaya
administrasi umum adalah gaji eksekutif puncak, biaya jasa konsultasi
hukum, pencetakan laporan tahunan, dan akuntansi umum. Biaya
penelitian dan pengembangan adalah biaya yang berkaitan dengan desain
dan pengembangan produk baru.
Menurut Rudianto (2005, h.14) perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang
membeli bahan mentah, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai dan
menjualnya kepada konsumen yang membutuhkannya. Misalnya produsen mie instan
mengolah tepung terigu hingga menjadi mie instan dan menjualnya kepada masyarakat.
Jadi, fungsi utama perusahaan manufaktur adalah sebagai jembatan antara perusahaan
penghasil bahan mentah dengan konsumen yang membutuhkan barang yang memiliki
25
nilai tambah lebih tinggi dari bahan mentah tersebut. Perusahaan manufaktur harus
mengolah terlebih dahulu bahan baku atau bahan mentah yang dibelinya sebelum
menjualnya ke masyarakat. Dalam proses pengolahan tersebut perusahaan manufaktur
membutuhkan biaya tambahan dalam berbagai bentuknya agar proses pemberian nilai
tambah dapat terjadi.
Karena, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli dan mengolah
bahan baku menjadi barang yang siap pakai maka secara keseluruhan transaksi di
perusahaan manufaktur dapat di ringkas ke dalam bagan sebagai berikut :
Menjual bahan Membeli bahan
Menjual produk jadi
Membeli produk
Gambar 2.1 Transaksi Perusahaan Manufaktur Sumber : Rudianto (2005,h.15)
Biaya di dalam perusahaan manufaktur dikelompokkan menjadi beberapa
kelompok menurut spesifikasi manfaatnya, yakni biaya bahan baku, biaya tenaga kerja
langsung, biaya overhead, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum.
1. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku
yang telah digunakan untuk menghasilkan suatu produk jadi dalam volume
tertentu. Misalnya, harga beli kain per potong pakaian, harga beli dari kayu
per unit meja dan sebagainya.
Produsen bahan baku
Perusahaan manufaktur
Konsumen
26
2. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar
pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Misalnya ,
tukang jahit di dalam perusahaan garmen, tukang kayu di dalam perusahaan
mebel dan lain-lain. Hanya pekerja yang terlibat secara langsung di dalam
proses menghasilkan produk perusahaan yang dapat dikelompokkan sebagai
tenaga kerja langsung.
3. Biaya overhead adalah berbagai macam biaya selain biaya bahan baku
langsung dan biaya tenaga kerja langsung tetapi juga dibutuhkan dalam
proses produksi. Termasuk dalam kelompok ini adalah biaya bahan
penolong, biaya tenaga kerja penolong dan biaya pabrikase lain.
1) Biaya bahan penolong (bahan tidak langsung) yaitu dalam bahan
tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk tertentu.
Misalnya, kain dan kancing dibutuhkan untuk menghasilkan pakaian,
paku dan cat untuk menghasilkan meja tulis dan sebagainya. Bahan
penolong merupakan elemen bahan baku yang tetap dibutuhkan oleh
suatu produk jadi tetapi bukan elemen utama. Tanpa bahan penolong,
suatu produk tidak akan pernah menjadi produk yang siap dipakai dan
siap dijual
2) Biaya tenaga kerja penolong (tenaga kerja tidak langsung) adalah pekerja
yang dibutuhkan dalam proses menghasilkan suatu barang tetapi tidak
terlibat secara langsung di dalam proses produksi. Misalnya, mandor dari
para penjahit dan tukang kayu, satpam pabrik dan lainnya. Tenaga kerja
penolong merupakan tenaga kerja yang tetap dibutuhkan tetapi bukan
27
merupakan elemen tenaga kerja utama didalam suatu produk. Tetapi
tanpa tenaga kerja penolong, proses produksi dapat terganggu.
3) Biaya pabrikase lain adalah biaya-biaya tambahan yang dibutuhkan untuk
menghasilkan suatu produk selain biaya bahan penolong dan biaya tenaga
kerja penolong. Seperti biaya listrik dan air pabrik, biaya telepon pabrik,
depresiasi bangunan pabrik, biaya depresiasi mesin dan sebagainya.
4. Biaya pemasaran digunakan untuk menampung keseluruhan biaya yang
dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan barang dagangannya hingga
sampai ke tangan langganan. Biaya ini mencakup, gaji salesman, komisi
salesman, biaya iklan, biaya listrik kantor pemasaran, biaya telepon kantor
pemasaran, biaya angkut penjualan, biaya depresiasi kantor dan kendaraan
pemasaran dan sebagainya.
5. Biaya administrasi dan umum digunakan untuk menanpung keseluruhan biaya
operasi kantor. Biaya ini mencakup, gaji direktur, gaji sekretaris, biaya
listrik, biaya telepon, biaya depresiasi bangunan dan lainnya.
Kemudian biaya-biaya tersebut diatas dikelompokkan lagi menjadi :
1). Biaya produksi
1. Biaya bahan baku langsung
2. Biaya tenaga kerja langsung
3. Biaya overhead
Akumulasi dari ketiga kelompok biaya tersebut di dalam satu periode
akuntansi menghasilkan biaya produksi untuk periode tersebut
28
2). Biaya operasi/komersial
1. Biaya pemasaran, dan
2. Biaya administrasi dan umum
Biaya operasi adalah biaya yang berkaitan dengan operasi perusahan diluar
biaya produksi. Biaya operasi atau biaya komersial mencakup dua
kelompok biaya yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum.
2.5.4 Jenis Persediaan Pada Perusahaan Manufaktur
Jenis persediaan (stok) dalam perusahaan manufaktur dapat dibedakan menjadi :
1. Persediaan bahan baku, yaitu bahan dasar yang menjadi komponen utama
dari suatu produk. Bahan baku merupakan elemen utama dari suatu produk,
walaupun di dalam suatu produk dalam terdapat elemen yang lain. Misalnya,
kain adalah bahan baku dari pakaian, kayu adalah bahan baku dari meja.
2. Persediaan barang dalam proses, yaitu bahan baku yang telah diproses untuk
diubah menjadi barang jadi, tetapi sampai pada akhir periode tertentu, belum
selesai proses produksinya. Misalnya, pakaian yang belum ada lengannya di
dalam industri garmen, meja tulis yang belum dihaluskan dan belum dicat
dalam industri mebel
3. Persediaan barang jadi, adalah bahan baku yang telah diproses menjadi
produk jadi yang siap pakai dan siap dipasarkan. Seperti pakaian jadi, meja
tulis, sepeda motor lengkap, televisi dan lain-lain. Perbedaan antara barang
jadi dan barang dalam proses adalah pada kandungan biaya di dalam setiap
jenis persediaan tersebut. Di dalam barang jadi terkandung 100 % komponen
29
biaya yang dibutuhkan, sedangkan barang dalam proses kandungan biayanya
kurang dari 100% dari keseluruhan biaya yang dibutuhkan.
2.5.5 Arus Biaya
Perusahaan manufaktur harus mengubah dan memproses bahan baku menjadi
barang dalam proses dan kemudian menjadi barang jadi, sedangkan biaya yang
dibutuhkan di dalam proses produksi tersebut terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga
kerja langsung dan biaya overhead maka hubungan antara setiap komponen biaya
tersebut dengan setiap jenis persediaannya, adalah sebagai berikut :
Gambar 2.2 Arus Biaya Sumber : Rudianto (2005,h.20)
Gabungan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya
overhead membentuk biaya produksi. Jika ketiga komponen biaya tersebut masing-
masing belum mencakup 100% dari kebutuhan biaya produksi per unit output maka
gabungan ketiganya membentuk persediaan barang dalam proses. Jika gabungan ketiga
komponen biaya tersebut masing-masing telah mencapai 100% maka akan membentuk
barang jadi. Itu berarti perbedaan antara barang jadi dan barang dalam proses adalah
pada kandungan biaya di dalam setiap jenis persediaan tersebut. Di dalam barang jadi
Bahan baku
Tenaga kerja
Overhead
Barang Dalam Proses
Barang Jadi
30
telah terkandung 100% komponen biaya yang dibutuhkan sedangkan barang dalam
proses kandungan biayanya kurang dari 100% dari keseluruhan biaya yang dibutuhkan
Ilustrasi berikut mungkin dapat memperjelas keterangan di atas:
PT Sandang Indah adalah sebuah perusahaan produsen pakaian jadi yang
berkedudukan di Bandung. Bahan baku yang digunakan di dalam perusahaan ini adalah
kain, sedangkan bahan penolongnya adalah kancing, benang, dan aksesoris. Tukang
jahitnya adalah tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses produksi. Di dalam
perusahaan ini, lokasi kantor administrasi, kantor pemasaran dan pabrik terpisah satu
dengan yang lain. Pada akhir bulan September 2002, staf akuntansi yang baru
menyusun suatu neraca saldo seperti berikut :
Tabel 2.1 Biaya PT Sandang Indah September 2002
Nama Biaya Jumlah (dalam jutaan)
Biaya pemakaian kain 97.000Biaya pemakaian kancing 4.700Biaya pemakaian benang 9.900Biaya pemakaian asesoris 6.600Upah tukang jahit 27.000Gaji mandor produksi 4.700Gaji satpam pabrik 1.200Gaji salesman 2.000Komisi salesman 6.000Gaji karyawan kantor pemasaran 8.200Gaji karyawan administrasi 7.400Biaya listrik, air, dan telepon pabrik 7.400Biaya listrik, air dan telepon kantor pemasaran 3.400Biaya listrik, air dan telepon kantor administrasi 4.700Biaya bunga 14.500Biaya depresiasi bangunan pabrik 2.600Biaya depresiasi bangunan kantor pemasaran 1.200Biaya depresiasi gedung kantor administrasi 1.300Biaya depresiasi mesin pabrik 2.600Biaya depresiasi kendaraan pemasaran 900Biaya depresiasi kendaraan direksi 700
31
Biaya angkut penjualan 2.900Biaya iklan 9.400Sumber : Rudianto (2005,22)
Berdasarkan data diatas, jika kemudian biaya-biaya tersebut dikelompokkan ke
dalam kelompok biaya sesuai dengan penjelasan di atas akan dapat terlihat hasilnya
sebagai berikut :
Tabel 2.2 Klasifikasi Biaya PT Sandang Indah September 2002
Nama Biaya Jumlah Biaya (dalam jutaan)
Total Biaya (dalam jutaan)
1. Biaya pemakaian kain 97.0002. Upah tukang jahit 27.0003. Biaya overhead :
a. Biaya bahan penolong : - Biaya pemakaian kancing - Biaya pemakaian benang - Biaya pemakaian asesoris
b. Biaya tenaga kerja penolong : - Gaji mandor peoduksi - Gaji satpam pabrik
c. Biaya pabrikase lain : - Biaya air, listrik, telepon - Biaya depresiasi bangunan - Biaya depresiasi mesin
4.700 9.900 6.600
4.700 1.200
7.400 2.600 2.600
21.200
5.900
12.600Biaya Produksi 163.7004. Biaya komersial :
a. Biaya pemasaran : - Gaji Salesman - Komisi salesman - gaji karyawan kantor pemasaran - Biaya listrik, air dan telepon - Biaya depresiasi kantor pemasaran - Biaya depresiasi kendaraan - Biaya angkut penjualan - Biaya iklan
2.000 6.000 8.200 3.400 1.200
900 2.900 9.400 34.000
b. Biaya administrasi dan umum : - Gaji karyawan administrasi - Biaya listrik, air, dan telepon - Biaya depresiasi kantor administrasi - Biaya depresiasi kendaraan
7.400 4.700 1.300
700
32
- Biaya bunga 14.500 28.600Total 62.600Sumber : Rudianto (2005,23)
2.5.6 Pembebanan Biaya Overhead Pabrik
Hansen dan Mowen (2009, h.162) mendefinisikan bahwa ada lima pendorong
kegiatan yang umumnya dipakai sebagai pembebanan biaya overhead :
1. Unit yang diproduksi
2. Jam tenaga kerja langsung
3. Dolar tenaga kerja langsung
4. Jam mesin
5. Bahan langsung
Biaya overhead seharusnya dibebankan mengikuti, sedekat mungkin, hubungan
sebab akibat. Untuk mengidentifikasikan faktor-faktor tersebut memerlukan usaha yang
menyebabkan konsumsi overhead. Faktor-faktor penyebab ini diidentifikasi, atau
pendorong kegiatan, harus digunakan untuk membebankan biaya overhead pada produk
Menurut Carter (2009, h.452), memberikan contoh pembebanan biaya overhead
yaitu :
Tarif overhead pabrik telah di tentukan sebelumnya yaitu sebesar $15 per jam
mesin dan estimasi pemakaian mesin selama 18.900 jam mesin. Untuk menentukan
ilustrasi ini, asumsikan jam mesin aktualnya adalah sebesar 18.000 jam mesin dan biaya
overhead pabrik aktual sebesar $292.000. Overhead pabrik yang dibebankan selama
periode ini adalah 18.900 x $15 = $283.500. Ayat jurnal umum yang mengikhtisarkan
pembebanan overhead adalah :
33
Barang dalam proses 283.500
Overhead pabrik dibebankan 283.500
Akun overhead pabrik dibebankan kemudian akan ditutup ke akun pengendali
overhead di akhir tahun dengan ayat jurnal sebagai berikut :
Overhead pabrik dibebankan 283.500
Pengendali overhead pabrik 283.500
Merupakan praktik umum untuk menggunakan overhead pabrik dibebankan
karena akun tersebut menyimpan biaya yang dibebankan dan biaya aktual secara
terpisah. Pemisahan ini menfasilitasi perbandingan bulanan dengan biaya overhead
pabrik yang dianggarkan.
Debit di akun pengendali overhead mencerminkan biaya overhead pabrik aktual
yang terjadi selama periode tersebut, sementara kreditnya mencerminkan jumlah yang
dibebankan. Mungkin juga penyesuaian kredit (misalnya, untuk retur perlengkapan ke
gudang) yang mengurangi biaya total overhead pabrik aktual. Karena debit dan
kreditnya jarang sama, maka biasanya ada saldo debit dan kredit di akun tersebut. Saldo
debit mengindikasikan bahwa overhead pabrik terlalu rendah, sedangkan saldo kredit
berarti bahwa overhead pabrik telah dibebankan terlalu tinggi. Saldo ini dapat
digunakan berbagai sumber informasi bagi manajemen untuk mengendalikan dan
menilai efisiensi operasi dan penggunaan kapasitas yang tersedia, serta untuk
34
menghitung tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya untuk periode-periode
berikutnya.
Alokasi pembebanan yang terlalu tinggi dan terlalu rendah cukup sederhana. Di
akhir periode akuntansi, jumlah tersebut dapat diperlakukan sebagai biaya periodik atau
dialokasikan ke persediaaan dan harga pokok penjualan. Jika jumlah perbedaannya
tidak signifikan maka sebaiknya ditutup langsung ke ikhtisar rugi laba atau harga pokok
penjualan sebagai biaya periodik, contoh ayat jurnalnya adalah :
Ikhtisar laba rugi 8,500
Pengendali overhead pabrik 8.500
Atau
Harga pokok penjualan 8,500
Pengendali overhead pabrik 8,500
Tidak signifikan dalam hal ini mengacu pada jumlah yang sangat kecil sehingga
dampaknya ke laba apabila dibebankan seluruhnya, dibandingkan dengan
mengalokasikan sebagai persediaan, adalah tidak material yaitu sangat kecil sehingga
selisihnya diperkirakan tidak akan mempengaruhi keputusan atau pembaca laporan
keuangan.
2.6 Harga Pokok Produksi (HPP)
2.6.1 Pengertian Harga Pokok Produksi
Menurut Garrison, Norren dan Brewer (2008, p.47), harga pokok produksi terdiri
dari biaya manufaktur yang berkaitan dengan barang-barang yang diselesaikan dalam
periode tertentu
35
Menurut Horngren dan Datar (2009, p.65) mendefinisikan harga pokok produksi
mewakili jumlah biaya barang yang diselesaikan pada periode tersebut.
Hansen dan Mowen (2009, h.60) mendefinisikan harga pokok produksi
mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Biaya
yang hanya dibebankan ke barang yang diselesaikan adalah biaya manufaktur bahan
langsung, tenaga kerja langsung dan overhead.
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa harga pokok produksi
merupakan biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan pada proses produksi untuk
memperoleh barang dan jasa yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja
langsung dan biaya overhead pabrik.
2.6.2 Unsur-Unsur Harga Pokok Produksi
Menurut Carter (2009,p.40) unsur-unsur harga pokok produksi ada 3 yaitu :
1. Biaya Bahan Baku Langsung (Direct Material Cost) adalah semua bahan
baku yang membentuk bagian integral dari produk jadi dan dimasukkan
secara eksplisit dalam perhitungan biaya produk
2. Biaya Tenaga kerja langsung (Direct Labor Cost) adalah tenaga kerja yang
melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat
dibebankan secara layak ke produk tertentu
3. Biaya Overhead Pabrik (Factory Overhead) disebut juga overhead
manufaktur, beban manufaktur atau beban pabrik, terdiri atas semua biaya
manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke output.
36
2.6.3 Metode Penentuan Harga Pokok Produksi
Menurut Garrison dan Norren (2006, h.388) ada dua metode penentuan harga
pokok produksi, yaitu :
1. Perhitungan Biaya Penyerapan
Perhitungan biaya penyerapan (absorption costing) memperlakukan semua
biaya produksi sebagai biaya produk, tanpa membedakan apakah biaya itu
variabel atau tetap. Dengan demikian biaya produk per unit terdiri atas bahan
baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel dan tetap.
Karena perhitungan biaya penyerapan melibatkan semua produksi, metode
ini sering disebut sebagai metode biaya penuh (full cost).
2. Perhitungan Biaya Variabel
Perhitungan biaya variabel (variable costing), hanya biaya produksi yang
berubah ubah sesuai dengan output yang diperlakukan sebagai biaya produk.
Termasuk di dalamnya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead
pabrik variabel. Biaya overhead pabrik tetap tidak diperlakukan sebagai
biaya produk dalam metode ini. Sebaliknya, biaya overhead pabrik
diperlakukan sebagai biaya periodik, seperti beban administrasi dan
penjualan, beban tersebut dibebankan secara utuh ke dalam pendapatan setiap
periodenya. Perhitungan biaya variabel sering disebut perhitungan biaya
langsung (direct costing) atau perhitungan biaya marginal (marginal costing).
37
Menurut Witjaksono (2006,h.25) secara garis besar terdapat dua macam
alternatif sistem perhitungan harga pokok produksi antara lain :
1. Sistem Perhitungan Harga Pokok Penuh (Full Costing/Absorption Costing)
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), perusahaan manufaktur
diwajibkan untuk menerapkan metode perhitungan harga pokok penuh (full
absorption costing) untuk keperluan pelaporan pada pihak eksternal. Dalam
sistem harga pokok penuh seluruh biaya produksi variabel dan biaya
produksi tetap dibebankan kepada produk.
2. Sistem Perhitungan Harga Pokok Variabel (Variable Costing)
Dalam sistem harga pokok variabel (variable costing) hanya biaya produksi
variabel yang dibebankan kepada produk. Metode variable costing banyak
diterapkan bagi keperluan pelaporan internal, karena metode ini dianggap
konsisten dengan asumsi perilaku biaya yang kerap digunakan dalam
pengambilan keputusan manajemen.
2.6.4 Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi
Garrison, Noreen dan Brewer (2008, p.92) menyatakan bahwa terdapat dua
metode perhitungan biaya, yaitu :
1. Perhitungan biaya berdasarkan proses
Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses digunakan dalam perusahaan
yang memproduksi satu jenis produk dalam jumlah besar dalam jangka
panjang. Prinsip dasar dari perhitungan biaya berdasarkan proses adalah
mengakumulasikan biaya dari operasi atau departemen tertentu selama satu
38
periode penuh (bulanan, kuartalan, dan tahunan) dan kemudian membaginya
dengan jumlah ini yang diproduksi selama periode tersebut. Rumus dasar
untuk perhitungan biaya berdasarkan proses adalah sebagai berikut :
Biaya per unit = Total biaya produksi
Total unit yang diproduksi
Secara umum teknik perhitungan biaya tersebut berarti bahwa setiap biaya
rata-rata per unit yang ditetapkan untuk unit yang homogen mengalir secara
terus menerus sepanjang proses produksi.
2. Perhitungan biaya berdasarkan pesanan
Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan digunakan untuk perusahaan
yang memproduksi berbagai produk selama periode tertentu. Dalam sistem
perhitungan biaya berdasarkan pesanan, biaya ditelusuri dan dialokasikan ke
pekerjaan dan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dibagi dengan
jumlah unit yang dihasilkan untuk menghasilkan harga rata-rata per unit.
Carter (2009, h.124) mendefinisikan bahwa ada dua metode penentuan harga
pokok penjualan, yaitu :
1. Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan (Job Order Costing)
Dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan, biaya diakumulasikan untuk
setiap batch, lot, atau pesanan pelanggan. Dalam perhitungan biaya,
berdasarkan pesanan akan lebih praktis mengidentifikasikan secara fisik
setiap pesanan yang diproduksi dan membebankan setiap pesanan dengan
paling tidak beberapa elemen biayanya.
39
Dasar dari perhitungan biaya berdasarkan pesanan melibatkan hanya delapan
tipe ayat jurnal akuntansi, satu untuk setiap item berikut :
a. Pembelian bahan baku
b. Pengakuan biaya tenaga kerja pabrik
c. Pengakuan biaya overhead pabrik
d. Penggunaan bahan baku
e. Distribusi beban gaji tenaga kerja
f. Pembebanan estimasi biaya overhead
g. Penyelesaian pesanan
h. Penjualan produk
2. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses (Process Costing)
Perhitungan biaya berdasarkan proses mengakumulasikan semua biaya
operasi suatu proses untuk periode waktu dan kemudian membagi biaya
tersebut dengan jumlah unit produk yang telah melewati proses selama
periode tersebut hasilnya adalah biaya per unit.
Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, bahan baku, tenaga
kerja dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya. Biaya yang
dibebankan ke setiap unit ditentukan dengan membagi total biaya yang
dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi. Pusat biaya
biasanya adalah departemen, tetapi bisa juga pusat pemrosesan dalam satu
departemen. Persyaratan utamanya adalah semua produk yang diproduksi
dalam suatu pusat biaya selama suatu periode harus sama dalam hal sumber
40
daya yang dikonsumsi; bila tidak, perhitungan biaya berdasarkan proses
dapat mendistorsi biaya produk
2.7 Harga Jual
2.7.1 Pengertian Harga Jual
Garisson, Noreen dan Brewer (2006, h.531) menyatakan, “Keputusan penentuan
harga jual sangat penting bagi perusahan. Jika harga jual ditentukan terlalu tinggi,
konsumen akan enggan untuk membeli produk perusahaan. Jika harga jual yang
ditentukan terlalu rendah, biaya perusahaan tidak mungkin tertutupi.”
Pendekatan umum penentuan harga jual adalah mark up. Mark up adalah
perbedaan antara harga jual dan biaya produksinya
Harga jual = Biaya + (Persentase mark up x biaya)
Menurut Rudianto (2005,h.230), harga jual produk perusahaan sangat
berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Harga jual
terlalu tinggi akan membuat masyarakat tidak membeli atau mengurangi jumlah
pembelian produk perusahaan sehingga perusahaan tidak akan memperoleh pendapatan
dan laba yang cukup. Sebaliknya, harga jual yang terlalu rendah akan membuat
perusahaan tidak mampu mencapai laba usaha yang direncanakan. Karena itu,
menetapkan harga jual produk perusahaan pada harga yang sangat tepat sangat penting
bagi perusahaan agar tujuan perusahaan secara umum dapat tercapai.
41
2.7.2 Metode Penentuan Harga Jual
Garrison, Noreen dan Brewer (2006, h.537) mengatakan terdapat 2 pendekatan
dalam menentukan harga jual yaitu :
1. Pendekatan absorption costing untuk cost plus pricing
Berdasarkan pendekatan absorption terhadap cost plus pricing, basis
biayanya adalah biaya produksi per unit berdasarkan absorption costing.
Untuk menggambarkan hal tersebut asumsikan bahwa pihak manajemen
Ritter Company ingin menentukan harga jual produk yang baru saja
dimodifikasi. Departemen Akuntansi memberikan estimasi biaya untuk
desain ulang produk seperti yang tersaji dibawah ini :
Per unit Total
Bahan Langsung $6
Tenaga Kerja Langsung 4
Overhead pabrik tetap 3
Overhead pabrik variabel $ 70,000
Biaya admin, umum dan penjualan variable 2
Biaya admin, umum dan penjualan tetap 60.000
Langkah pertama dalam pendekatan absorption costing untuk cost plus
pricing untuk menghitung biaya produksi per unit. Untuk Ritter Company,
nilainya adalah $20 per unit dengan volume 10.000 unit seperti tampak
dalam perhitungan di bawah ini :
42
Bahan Langsung $6
Tenaga Kerja Langsung 4
Overhead pabrik variable 3
Overhead pabrik tetap 7
Biaya Produksi per unit $20
Ritter Company memiliki kebijakan umum mark up biaya produksi per unit
sebesar 50 %.
Mark up untuk menutup biaya administrasi, umum dan penjualan dan laba
yang diharapkan adalah 50 % dari biaya produksi per unit 10
Target harga jual per unit $30
Masalah masalah dalam pendekatan absorption costing yang harus dilakukan
adalah menghitung biaya produksi per unit, memutuskan berapakah laba
yang diinginkan, dan menentukan harga jual. Pendekatan absorption costing
mengandalkan perkiraan unit penjualan. Pendekatan absorption costing
mengasumsikan bahwa konsumen membutuhkan barang sebanyak yang
diperkirakan dan bersedia membayar berapa harga jual yang telah ditetapkan.
Dalam kenyataannya, konsumen memiliki pilihan. Jika harga jual ditentukan
terlalu tinggi, mereka dapat membeli dari pesaing atau bahkan tidak membeli
sama sekali. Pendekatan absorption costing hanya aman sepanjang
konsumen bersedia membeli sejumlah barang seperti yang telah diperkirakan
2. Target Costing
Perhitungan biaya target adalah proses penentuan biaya maksimum yang
dimungkinkan untuk suatu produk baru dan kemudian mengembangkan
43
sebuah contoh yang dapat dibuat dengan menguntungkan berdasarkan angka
biaya target maksimum tersebut.
Biaya target untuk suatu produk dihitung dengan mulai pada harga jual yang
diantisipasi dan kemudian menguranginya dengan laba yang diinginkan,
sebagai berikut :
Biaya target = Harga jual yang diantisipasi – Laba yang diinginkan
Untuk memperjelas lagi terdapat contoh sederhana :
Handy Appliance Company survey fitur dan harga sebesar $30 di pasar,
departemen marketing percaya bahwa harga $ 30 cocok untuk mixer baru
tersebut. Pada harga tersebut, marketing memperkirakan dapat menjual
40.000 unit mixer per tahun. Untuk mendesain, mengembangkan dan
memproduksi mixer baru ini, dibutuhkan investasi sebesar $ 2.000.000.
Perusahan mengharapkan Return on Investment (ROI) 15%. Dengan data
tersebut, target biaya produksi, penjualan, distribusi dan jasa untuk per unit
mixer adalah $22,5 seperti dalam perhitngan berikut :
Proyeksi penjualan (50.000 mixer X $30) $ 1.200.000
Dikurangi laba yang diharapkan
(15% x $ 2.000.000) 300.000
Target biaya untuk 40.000 mixer $ 900.000
Target biaya untuk setiap unit mixer
($ 900.000 : 40.000) $ 22.5
44
Target biaya sebesar $ 22.5 ini akan dipilah menjadi target biaya beberapa
fungsi : produksi, marketing, distribusi, jasa setelah penjualan dan
sebagainya. Setiap area fungsional akan bertanggung jawab untuk
mengeluarkan biaya sesuai dengan target.
Menurut Rudianto (2005, h.232) secara umum terdapat beberapa metode yang
dapat dipergunakan untuk menentukan harga jual suatu produk dengan berbasis pada
besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan, yaitu :
1. Maksimalisasi laba
Untuk memperjelas keterangan tentang metode maksimalisasi di dalam
menetapkan harga jual produk di atas :
PT Koinmas memproduksi suatu barang dengan kapasitas sebesar 140.000
unit per tahun. Jumlah biaya tetap total yang akan dikeluarkan untuk
menghasilkan seluruh produk tersebut adalah sebesar Rp 300.000.000,00
sementara biaya variable yang diperlukan untuk menghasilkan produk
tersebut diperkirakan sebesar Rp 7.000,00 per unit. Manajemen perusahaan
sedang mempertimbangkan harga jual yang tepat untuk produk tersebut, agar
laba usaha total yang akan diperoleh perusahaan optimal. Bagian pemasaran
perusahaan akan memperkirakan perubahan harga produk akan
mempengaruhi secara langsung jumlah produk yang akan terjual. Taksiran
bagian pemasaran tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 2.3 Perkiraan Perubahan Harga Produk Terhadap Volume Penjualan
Harga jual (Rp) Volume (unit) 20.000,00 20.000 18.000,00 40.000
45
16.000,00 60.000 14.000,00 80.000 12.000,00 100.000 10.000,00 120.000 8.000,00 140.000
Sumber : Rudianto (2005,h.233)
Berdasarkan data tersebut di atas, manajemen PT Koinmas membuat tabel
alternatif harga dan volume penjualan sebagai berikut :
Tabel 2.4 Alternatif harga dan Volume Penjualan
Harga Jual
Volume Penjualan
Nilai Penjualan
Biaya Variabel
Biaya Tetap Laba (Rugi)
20.000 20.000 400.000.000 140.000.000 300.000.000 - 40.000.000 18.000 40.000 720.000.000 280.000.000 300.000.000 140.000.000 16.000 60.000 960.000.000 420.000.000 300.000.000 240.000.000 14.000 80.000 1.120.000.000 560.000.000 300.000.000 260.000.000 12.000 100.000 1.200.000.000 700.000.000 300.000.000 200.000.000 10.000 120.000 1.200.000.000 840.000.000 300.000.000 60.000.000 8.000 140.000 1.120.000.000 980.000.000 300.000.000 160.000.000
Sumber : Rudianto (2005,h.234)
Itu berarti, harga jual yang optimal yang dapat mengakibatkan perolehan laba
usaha maksimal adalah sebesar Rp 14.000 per unit produk.
2. Tingkat pengembalian atas modal yang digunakan
Terkadang perusahaan menetapkan terlebih dahulu besarnya tingkat
pengembalian atas modal yang ditanamkannya di dalam suatu bidang usaha,
sebagai dasar untuk menentukan harga jual produk yang dihasilkan
perusahaan tersebut.
Ilustrasi berikut mungkin dapat memperjelas keterangan dalam metode tingkat
pengembalian atas modal di dalam menetapkan harga jual produk di atas.
PT. Prima Niaga adalah sebuah perusahaan produsen pemanas air listrik.
Total modal yang digunakan oleh perusahaan ini adalah sebesar Rp
46
500.000.000,00 dengan tingkat pengembalian invenstasi atas modal yang
digunakan adalah sebesar 20 %. Volume produksi dan volume penjualan
yang direncanakan adalah sebesar 50.000 unit produk. Sementara biaya yang
dikeluarkan untuk memproduksi seluruh produk adalah sebesar Rp
320.000.000,00. Berdasarkan tingkat pengembalian investasi atas modal yang
digunakan tersebut maka harga jual per unit pemanas air listrik adalah sebagai
berikut :
Harga = total biaya + (tingkat pengembalian modal x modal)
Volume penjualan
= 320.000.000 + (20% x 500.000.000)
50.000
= Rp 8.400,00 per unit
Bukti :
Penjualan = 50.000 unit x Rp 8.400 = Rp 420.000.000
Total biaya = Rp 320.000.000
Laba = 20 % x Rp 500.000.000 = Rp 100.000.000
Berdasarkan perhitungan diatas, terlihat bahwa dengan tingkat pengembalian
atas modal yang ditanamkan sebesar 20 % maka harga jual yang ditetapkan
untuk pemanas air listrik adalah sebesar Rp 8.400,00 per unit. Dari
perhitungan pembuktian di atas, terlihat bahwa dengan harga Rp 8.400,00 per
unit tersebut dan dengan volume penjualan sebesar 50.000 unit akan
menghasilkan laba usaha sebesar Rp 100.000.000,00. Laba sebesar Rp
100.000.000,00 tersebut merupakan 20 % dari total modal yang ditanamkan.
47
3. Biaya konversi
Jika suatu perusahaan memproduksi lebih dari satu produk dengan komposisi
biaya yang berbeda satu dengan yang lainnya maka perusahaan tersebut dapat
mempertimbangkan untuk membuat pilihan produksi yang paling
menguntungkan bagi perusahaan. Maksudnya, jika perusahaan memiliki 2
produk untuk dihasilkan dengan jumlah laba per per unit yang sama antara 1
produk dengan lainnya maka perusahaan harus melihat komposisi biaya
diantara kedua produk. Dengan melihat dan menganalisis komposisi biaya
masing-masing produk tersebut, perusahaan dapat memilih untuk
memproduksi salah satu produk saja yang memberikan keuntungan total yang
lebih besar dari perusahaan.
4. Marjin kontribusi
Marjin kontribusi adalah selisih antara harga jual dengan biaya produksi
variable yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Jumlah
tersebut akan digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba
periode tersebut. Marjin kontribusi bukanlah laba kotor usaha. Marjin
kontribusi dihitung dengan mengabaikan biaya tetap yang dikeluarkan
perusahaan. Jika perusahaan telah mencapai titik impas (break even point)
maka biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan pada periode tersebut telah
dibebankan dan ditutup oleh volume impas tersebut perusahan dapat
mengabaikan biaya tetap tersebut dalam menentukan harga jual produknya.
48
5. Biaya standar
Jika perusahaan telah memiliki biaya standar yang dijadikan tolak ukur
dalam menentukan besarnya biaya produksi maka penentuan harga jual dapat
pula ditentukan berdasarkan biaya standar yang dimiliki perusahaan.
Persoalannya, seringkali realisasi biaya produksi menyimpang dari biaya
standar yang dimiliki perusahaan. Jika terjadi penyimpangan realisasi biaya
produksi dari biaya standarnya maka harus segera diambil tindakan cepat
untuk merevisi keputusan harga jual yang telah ditetapkan.
Secara umum, terdapat 4 jenis perusahaan dulihat dari reaksi yang mereka
lakukan terhadap penyimpangan biaya standar, yaitu sebagai berikut :
a. Perusahaan yang tidak merevisi standar yang telah ditetapkannya,
walaupun terjadi penyimpangan didalam realisasi biaya produksi.
b. Perusahaan yang merevisi standar yang telah di tetapkannya dalam
batas tertentu, pada saat terjadi penyimpangan di dalam realisasi
biaya produksi
c. Perusahaan yang merevisi standar yang telah ditetapkannya agar lebih
sesuai dengan kondisi aktual, pada saat terjadi penyimpangan di
dalam realisasi biaya produksi.
d. Perusahaan menggunakan harga pasar, pada saat terjadi
penyimpangan terhadap realisasi biaya produksi.
49
2.7.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Jual
Horngren dan Datar (2006, p.398) menyatakan bahwa ada tiga faktor yang
mempengaruhi harga jual, yaitu :
1. Pelanggan
Pelanggan mempengaruhi harga melalui pengaruh mereka terhadap
permintaan atas suatu produk atau jasa. Perusahaan harus selalu menguji
keputusan penentuan harga melalui para pelanggan mereka. Harga yang
terlalu tinggi dapat menyebabkan pelanggan menolak suatu produk
perusahaan dan memilih produk pengganti atau yang bersaing.
2. Pesaing
Perusahaan harus selalu menyadari tindakan dari para pesaingnya. Pada satu
sisi, produk alternatif atau produk pengganti dari pesaing dapat
mempengaruhi permintaan dan memaksa sebuah perusahaan yang tidak
memiliki pesaing dapat menetapkan harga yang lebih tinggi.
3. Biaya
Biaya mempengaruhi harga karena biaya mempengaruhi karyawan. Makin
rendah biaya produksi sebuah produk relatif terhadap harga yang dibayarkan
pelanggan, semakin besar kuantitas produk yang bersedia ditawarkan oleh
perusahaan. Karena terdapat banyak pesaing dan banyak pelanggan, suatu
perusahaan atau seorang pelanggan tidak mempengaruhi harga. Jika
50
persaingan berkurang, dan terdapat lebih sedikit pesaing, yang masing-
masing menjual produk yang agak berbeda dari harga perusahaan lain.
Apabila perusahaan menjual barang atau jasa dengan harga jual dibawah
biaya produksi, maka perusahaan akan mengalami kerugian sedangkan
apabila perusahan menjual barang atau jasa di atas biaya produksi maka
perusahaan akan mudah menghitung laba yang akan diterima oleh
perusahaan.
Biasanya perusahaan memberikan harga yang baik agar dapat menjaga
hubungan dengan pelanggannya dalam jangka panjang dan jangka pendek.
Dalam menentukan harga jual perusahaan mengadakan analisis dalam
menentukan harga dasar. Analisis dilakukan perusahaan antara lain terhadap:
a. Harga pokok produksi yang dijadikan batas bawah dari harga jual
b. Informasi harga pasar yang dijadikan pedoman dalam menentukan harga
jual
c. Kemampuan produksi maksimum perusahaan dalm memenuhi kebutuhan
konsumen.
Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan yang mempengaruhi
perusahaan dalam menentukan harga jual adalah pelanggan, pesaing dan
biaya.
51
2.7.4 Titik Impas
Menurut Rudianto (2005, h.49) titik impas adalah volume penjualan yang harus
dicapai perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kerugian tetapi juga tidak
memperoleh laba sama sekali. Titik impas tersebut dapat diketahui dengan membagi
antara total biaya tetap dengan rasio margin kontribusi, itu berarti dapat ditulis dengan
rumus sebagai berikut :
Titik impas = 1 - Total biaya tetap/Biaya variabel
Penjualan
Ilustrasi berikut mungkin dapat semakin memperjelas keterangan tentang analisis
titik impas tersebut diatas :
PT ABC adalah sebuah perusahaan produsen biji plastik. Kapasitas produksi
perusahaan ini dalam satu tahun sebesar 1200 ton biji plastik. Untuk menghasilkan
produk dengan volume tersebut, biaya tetap dikeluarkan adalah sebesar Rp
360.000.000,00 sedangkan biaya variable yang dibutuhkan sebesar Rp
1.080.000.000,00. Harga jual biji plastik tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 per ton.
Berdasarkan data tersebut diatas, jika dihitung titik impasnya maka harus
dihitung terlebih dahulu biaya variabel per ton dari biji plastik tersebut. Biaya variabel
total untuk memproduksi 1200 ton biji plastik adalah sebesar Rp 1.080.000.000,00.
Maka, biaya variable yang dibutuhkan untuk memproduksi satu ton biji plastik adalah
sebesar 900.000,00 yaitu dari hasil membagi Rp 1.080.000.000,00 tersebut dengan 1.200
ton bijih plastik.
52
Kemudian dari data yang telah tersedia dapat dihitung volume titik impasnya
yaitu :
Titik impas = 1 – 900.000,00/1.500.000
= Rp 900.000.000,00
Angka sebesar Rp 900.000.000,00 tersebut diatas merupakan nilai penjualan
minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi sekaligus juga merupakan
nilai penjualan yang mengakibatkan perusahaan belum memperoleh keuntungan. Untuk
mengetahui volume penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, harus
dihitung dengan membagi nilai penjualan tersebut dengan harga jual setiap unit produk
tersebut :
Titik impas (dalam unit) = Titik impas dalam uang
Harga jual per unit produk
Titik impas (dalam unit) = Rp 900.000.000,00
Rp 1.500.000,00
= 600 ton
Pembuktian :
Laba = penjualan – biaya total
= penjualan – (biaya tetap + biaya variable)
= {(600 ton x Rp 1.500.000,00) }-{360.000.000,00 +(600 ton x 900.000,00)}
53
= 900.000.000,00 – (360.000.000,00 + 540.000.000,00)
= 0
Jadi, pada saat perusahan menjual produknya sebanyak 600 ton, perusahaan
memperoleh laba nol. Oleh karena itu, agar tidak mengalami kerugian, perusahaan
harus menjual minimal sebanyak 600 ton. Pada volume penjualan 600 ton ini, seluruh
biaya tetap sebesar Rp 360.000.000,00 telah ditutup.
Pendapatan dan Biaya BEP Total Biaya
900
360 Biaya Tetap
Q
600
Volume Penjualan
Gambar 2.3 Contoh Grafik Break Even Point
54
2.8 SWOT
2.8.1 Matriks IFE (The Internal Factor Evaluation)
Menurut David (2009, p229-232), Matriks Evaluasi Faktor Internal (Internal
Factor Evaluation – IFE Matrix) merupakan alat perumusan strategi yang digunakan
untuk meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area-area
fungsional bisnis dan menjadi landasan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi
hubungan di antara area tersebut.
Matriks Evaluasi Faktor Internal dapat dikembangkan dalam lima langkah:
1. Buat daftar faktor-faktor internal utama sebagaimana yang disebutkan dalam
proses audit internal. Masukkan 10 sampai 20 faktor internal, termasuk
kekuatan maupun kelemahan organisasi. Daftar terlebih dahulu
kekuatannya, kemudian kelemahannya. Buat sespesifik mungkin dengan
menggunakan persentase, rasio, dan angka-angka perbandingan.
2. Berilah pada setiap faktor tersebut bobot yang berkisar dari 0,0 (tidak
penting) sampai 1,0 (semua penting). Bobot yang diberikan pada suatu
faktor tertentu menandakan signifikansi relatif faktor tersebut bagi
keberhasilan industri perusahaan. Terlepas dari apakah faktor utama itu
adalah kekuatan atau kelemahan internal, faktor-faktor yang dianggap
memiliki pengaruh paling besar terhadap kinerja organisasional harus diberi
bobot tertinggi. Jumlah seluruh bobot harus sama dengan 1,0.
3. Berilah peringkat 1 sampai 4 pada setiap faktor untuk mengindikasikan
apakah faktor tersebut sangat lemah (peringkat = 1), lemah (peringkat = 2),
kuat (peringkat = 3), atau sangat kuat (peringkat = 4). Perhatikan bahwa
55
kekuatan harus mendapat peringkat 3 dan 4 dan kelemahan harus mendapat
peringkat 1 atau 2. Oleh karenanya, peringkat berbasis perusahaan,
sementara bobot di langkah 2 berbasis industri.
4. Kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor
bobot bagi masing-masing variabel.
5. jumlahkan skor bobot masing-masing variabel untuk memperoleh skor
bobot total organisasi.
2.8.2 Matriks EFE (The External Factor Evaluation)
Menurut David (2009, p.158), Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (External
Factor Evaluation – EFE Matrix) memungkinkan para penyusun strategi untuk
meringkas dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan
politik, pemerintahan, hukum, teknologi dan kompetitif.
Matriks Evaluasi Faktor Eksternal dapat dikembangkan dalam lima langkah:
1. Buat daftar faktor-faktor eksternal utama sebagaimana yang disebutkan
dalam proses audit eksternal. Masukkan 10 sampai 20 faktor internal,
termasuk peluang dan ancaman, yang memengaruhi perusahaan dan
industrinya. Daftar terlebih dahulu peluangnya, kemudian ancamannya.
Buat sespesifik mungkin dengan menggunakan persentase, rasio, dan angka-
angka perbandingan jika dimungkinkan.
2. Berilah pada setiap faktor tersebut bobot yang berkisar dari 0,0 (tidak
penting) sampai 1,0 (sangat penting). Bobot itu mengindikasikan
signifikansi relatif dari suatu faktor terhadap keberhasilan perusahaan.
56
Peluang sering kali mendapat bobot yang lebih tinggi daripada ancaman,
tetapi ancaman bisa diberi bobot tinggi terutama jika mereka sangat parah
atau mengancam. Bobot yang sesuai dapat ditentukan dengan cara
membandingkan pesaing yang berhasil dengan yang tidak berhasil atau
melalui diskusi untuk mencapai konsensus kelompok. Jumlah seluruh bobot
yang diberikan pada faktor itu harus sama dengan 1,0.
3. Berilah peringkat 1 sampai 4 pada setiap faktor untuk menunjukkan
seberapa efektif strategi perusahaan saat ini dalam merespons faktor
tersebut, di mana 4 = responsnya sangat bagus, 3 = responsnya di atas rata-
rata, 2 = responsnya rata-rata, dan 1 = responsnya di bawah rata-rata.
Peringkat didasarkan pada keefektifan strategi perusahaan. Oleh karenanya,
peringkat tersebut berbeda antarperusahaan, sementara bobot di langkah
nomor 2 berbasis industri. Penting untuk diperhatikan bahwa baik ancaman
maupun peluang dapat menerima peringkat 1,2,3 atau 4.
4. Kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor
bobot bagi masing-masing variabel.
5. jumlahkan skor bobot masing-masing variabel untuk memperoleh skor
bobot total organisasi.
2.8.3 Diagram SWOT
Setelah didapat hasil tabel bobot skor dari masing – masing IFAS dan EFAS,
langkah selanjutnya adalah memasukkan angka total bobot skor tersebut kedalam
diagram analisis SWOT berikut ini :
57
Gambar 2.4 Diagram Analisis SWOT (Sumber : Pearce & Robinson, (2008, p.203))
Keterangan (Pearce & Robinson, 2008, p.204-205) :
Kuadran I : Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan, perusahaan tersebut
memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang
yang ada, strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah
mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented
Strategy).
Kuadran II : Ini merupakan kuadran dimana perusahaan telah mengidenfitikasi
beberapa kekuatan inti menghadapi situasi lingkungan yang tidak
menjanjikan. Meskipun menghadapi berbagai ancaman, dalam situasi
ini perusahaan masih memiliki kekuatan segi internal, strategi yang
harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan
peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi
Oppurtunity(Beragam Peluang Lingkungan)
Strength(Kekuatan Yang Besar)
Weakness (Kelemahan Yang Penting)
Threat(Ancaman‐Ancaman Utama Lingkungan)
2. Mendukung Strategi Yang Agresif
3. Mendukung Strategi Diversifikasi
1. Mendukung Strategi YangBerorientasi Pada Perubahan
4. Mendukung Strategi YangDefensif
58
(produk/pasar) misalnya strategi untuk menggunakan sumber daya dan
kompetensi yang kuat tersebut unutk membangun peluang jangka
panjang pada pasar produk yang lebih menjanjikan.
Kuadran III : Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain
pihak ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus
strategi perusahaan adalah menghilangkan kelemahan internal
sehingga dapat lebih efektif dalam merebut peluang pasar yang lebih
baik.
Kuadran IV : Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan
tersebut menghadapi berbagai ancaman besar dari lingkungan karena
posisi sumber daya yang lemah (kelemahan internal). Situasi ini
membutuhkan strategi yang dapat mengurangi atau mengarahkan
kembali keterlibatan dalam produk atau pasar yang telah ditelaah
melalui analisis SWOT.
2.8.4 Matriks Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman (SWOT)
Matriks Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman (Strengths-Weaknesses-
Opportunities-Threats – SWOT) menurut David (2009, p.327), adalah sebuah alat
pencocokan yang penting yang membantu para manajer mengembangkan empat jenis
strategi : Strategi SO (kekuatan-peluang), Strategi WO (kelemahan-peluang), Strategi
ST (kekuatan-ancaman), dan Strategi WT (kelemahan-ancaman). Mencocokkan faktor-
faktor eksternal dan internal utama merupakan bagian tersulit dalam megnembangkan
Matriks SWOT dan membutuhkan penilaian yang baik dan tidak ada satu pun paduan
59
yang paling benar. Perhatikan Tabel 2.2 bahwa strategi pertama adalah strategi SO,
strategi kedua adalah strategi WO, strategi ketiga adalah strategi ST, dan strategi
keempat adalah strategi WT.
Strategi SO (SO Strategies) memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk
menarik keuntungan dari peluang eksternal. Strategi WO (WO Strategies) bertujuan
untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang
eksternal. Strategi ST (ST Strategies) menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk
menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Strategi WT (WT Strategies)
merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta
menghindari ancaman eksternal.
Matriks SWOT terdiri atas sembilan sel di mana terdapat empat sel faktor utama,
empat sel strategi dan satu sel yang dibiarkan kosong (sel kiri atas). Keempat sel
strategi, yang diberi nama SO, WO, ST, dan WT, dikembangkan setelah melengkapi
keempat sel faktor utama, yang diberi nama S, W, O, dan T.
60
Tabel 2.5 Matriks SWOT
KEKUATAN (STRENGTHS)
KELEMAHAN (WEAKNESS)
1 1 2 2 3 3 4 4 5 (Tulis Kekuatan) 5 (Tulis Kelemahan) 6 6 7 7 8 8
PELUANG (OPPORTUNITY)
STRATEGI SO
STRATEGI WO
1 1
1-8 (Gunakan Kekuatan Untuk Memanfaatkan
Peluang )
1
1-8 (Gunakan Kelemahan
Dengan Memanfaatkan
Peluang )
2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 (Tulis Peluang) 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8
ANCAMAN (THREATS)
STRATEGI ST
STRATEGI WT
1 1
1-8 (Gunakan Kekuatan Untuk
Menghindari Ancaman )
1
1-8 (Minimalkan kelemahan dan
Atasi Ancaman )
2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 (Tulis Ancaman) 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8
(Sumber: David, (2009, p.328))
Menurut David (2009, p.330), terdapat delapan langkah dalam membentuk sebuah
Matriks SWOT :
1. Buat daftar peluang-peluang eksternal utama perusahaan
2. Buat daftar ancaman-ancaman eksternal utama perusahaan
3. Buat daftar kekuatan-kekuatan internal utama perusahaan
61
4. Buat daftar kelemahan-kelemahan internal utama perusahaan
5. Cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal, dan catat hasilnya pada sel strategi
SO
6. Cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal, dan catat hasilnya pada sel Strategi
WO
7. Cocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal, dan catat hasilnya pada sel Strategi
ST
8. Cocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal, dan catat hasilnya pada sel
Strategi WT
2.9 Object Oriented Analysis and Design
Menurut Mathiassen et al. (2000, p.14), Object Oriented Analysis and Design
(OOAD) terbagi kedalam empat aktivitas, antara lain: analisis problem-domain, analisis
application domain, architecture design, dan component design.
Keuntungan dari OOAD adalah:
a. Menyediakan info yang jelas mengenai konteks sistem.
b. Ada kaitan yang erat antara object-oriented analysis, object-oriented design,
object-oriented user interface dan object-oriented programming.
Notasi standar yang digunakan dalam OOAD adalah UML (Unified Modeling
Languange). UML digunakan hanya sebagai notasi dan bukan sebagai metode dalam
melakukan modeling.
Gambar 2.5 dibawah ini merupakan ringkasan dari kegiatan yang dilakukan
dalam OOAD, yang menjelaskan bahwa dalam analisis problem domain akan
menghasilkan sebuah model, dalam analisis application domain akan menghasilkan
62
sebuah Requirement for use, dalam perancangan arsitektural akan dihasilkan spesifikasi
perancangan. Model, Requirement for use, dan spesifikasi perancangan ini yang akan
menjadi dasar dalam perancangan komponen dimana kegiatan ini akan menghasilkan
spesifikasi komponen.
Gambar 2.5 Kegiatan utama dan hasil dari Object Oriented Analysis and Design Sumber : Mathiassen, et.al. (2000, p.15)
Mengacu kepada Mathiassen et al. (2000, p.18), ada empat prinsip umum dalam
menganalisis dan merancang sebuah sistem yaitu:
1. Pemodelan konteks (Model the Context)
Konteks dari sebuah sistem dapat dilihat dari dua perspektif yang saling
melengkapi yaitu problem domain dan application domain. Problem domain
merupakan bagian dari konteks yang diatur, diawasi atau dikendalikan oleh
sebuah sistem. Application domain merupakan sebuah organisasi yang
63
mengelola, mengawasi atau mengendalikan suatu problem domain.
Kesuksesan dan kegagalan sebuah sistem tergantung dari seberapa baik
application domain dan problem domain terhubung bersama – sama ke
dalam fungsi keseluruhan.
Oleh karena itu, pemodelan dari problem domain dan application domain
merupakan hal yang mendasar selama kegiatan analisis dan perancangan
sistem.
2. Penekanan pada Arsitektur (Emphasize the Architecture)
Analisis dan perancangan berorientasi objek menekankan arsitektur sistem
sebagai sebuah tantangan utama, menfokuskan kepada kemudahan untuk
dipahami, fleksibilitas dan kegunaannya sebagai kualitas perancangan yang
penting. Sebuah arsitektur sistem harus mudah untuk dipahami karena
menyediakan sebuah dasar bagi keputusan dan sebagai alat komunikasi serta
alat kerja pada tugas pengembangan selanjutnya. Arsitektur sistem harus
fleksibel karena pengembangan sistem terjadi pada lingkungan yang
bergejolak. Terakhir, arsitektur sistem harus dapat bermanfaat karena
kesuksesan sebuah sistem tergantung dari bagaimana sistem dapat berperan
dalam organisasi pengguna.
Dalam analisis dan perancangan berorientsi objek, ada tiga komponen
arsitektur dasar yaitu : model component, function component dan interface
component. Model component berisi sebuah model dinamis dari problem
domain sistem. Function component berisi fasilitas – fasilitas bagi user
untuk melakukan update dan mengunakan model component. Interface
64
component merangkaikan sistem ke dalam konteksnya dengan dua cara. Cara
pertama, interface mencakup monitor dengan teks dan grafik – grafik,
printouts, dan fasilitas lain yang membuat user dapat mengaktifkan fungsi –
fungsi sistem. Cara kedua, interface terhubung secara langsung dengan
teknikal sistem lain seperti radar dan sensor.
3. Penggunaan kembali Pola – Pola (Reuse Patterns)
Cara mendasar untuk memastikan kualitas dan efisiensi dalam analisis dan
perancangan adalah dengan menggunakan kembali ide-ide yang telah diuji
dan digunakan dalam situasi – situasi lain. Analisis dan perancangan
berorientasi objek menginspirasikan penggunaan kembali ini dengan dua
cara, yaitu dengan menggunakan objek dan komponen dan dengan
menggunakan pola analisis dan perancangan.
4. Penyesuaian Metode (Tailor the Method)
OOAD adalah kumpulan dari pedoman umum untuk melakukan analisis dan
perancangan sistem. Oleh sebab itu, harus dilakukan penyesuaian terhadap
organisasi dan proyek. Untuk membuat metode lebih berguna, perancangan
harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga adaptasi, perbaikan, dan
penggantian bagian lebih mudah untuk diimplementasikan.
OOAD merefleksikan empat perspektif sentral pada suatu sistem dan
konteksnya, yaitu isi informasi dari sistem, bagaimana sistem akan
digunakan, sistem sebagai keseluruhan dan komponen – komponen dari
sistem. Perpektif – perspektif tersebut terhubung dengan aktivitas – aktivitas
utama dari analisis dan perancangan berorientasi objek, yaitu problem
65
domain analysis, application domain analysis, architectural design dan
component design, secara berturut – turut.
2.9.1 Object
Menurut Mathiassen et al. (2000, p.4) objek adalah sebuah entity dengan
identitas, state dan behaviour. Setiap objek tidak digambarkan secara sendiri - sendiri,
melainkan istilah class digunakan untuk menggambarkan kumpulan objek.
Dengan demikian dapat dikatakan, karakteristik dari objek adalah sebuah entitas,
melekat pada identitasnya, dan memiliki behaviour masing-masing.
2.9.2 System Choice dan System Definition
Pemilihan sistem dilakukan untuk menghasilkan system definition yang
memenuhi kriteria FACTOR.
Menurut Mathiassen et al. (2000,p.24), system definition adalah sebuah
deskripsi singkat dari sistem yang terkomputerisasi yang dijelaskan dalam bahasa
natural. Tujuan dari system definition adalah untuk memilih sistem aktual yang akan
dikembangkan.
System definition di sini dapat berupa narasi singkat mengenai sistem yang akan
dikembangkan mencakup kegunaan dan kebutuhan dari sistem yang akan dikembangkan
agar dapat memenuhi kebutuhan informasi dalam perusahaan.
66
Rich Picture
Menurut Mathiassen et al. (2000, p.26), rich picture adalah sebuah gambaran
informal yang digunakan oleh pengembang sistem untuk menyatakan pemahaman
mereka terhadap situasi dari sistem yang sedang berlangsung. Rich picture juga dapat
digunakan sebagai alat yang berguna untuk memfasilitasi komunikasi yang baik antara
pengguna dalam sistem. Tujuan dari pembuatan rich picture bukan untuk membuat
deskripsi yang mendetail dari semua keadaan yang mungkin, tetapi lebih untuk
memperoleh gambaran umum.
Rich picture merupakan tahap pertama yang dilakukan dalam analisis dan
perancangan sistem, karena melalui rich picture dapat diketahui proses berjalan dari
sistem yang akan dikembangkan sehingga akan memudahkan pengembang sistem untuk
mendefinisikan kebutuhan dari sistem tersebut.
FACTOR Criteria
Menurut Mathiassen et al. (2000,p.39), FACTOR terdiri dari 6 elemen yaitu :
Tabel 2.6 Tabel FACTOR Criteria Functionality Fungsi sistem yang mendukung application domain. Application domain Bagian dari organisasi, administrasi, monitor, atau
kontrol problem domain. Conditions Kondisi setelah sistem akan dikembangkan dan
digunakan. Technology Teknologi yang digunakan dalam pengembangan
sistem dan teknologi yang akan menjalankan sistem. Objects Object utama dalam problem domain. Responsibility Tanggung jawab keseluruhan sistem dalam
hubungannya dengan context.” Sumber : Mathiassen et al. (2000,p.39)
67
2.9.3 Problem Domain Analysis
Menurut Mathiassen et al. (2000, p.6) problem domain merupakan bagian dari
context yang diatur, dimonitor, atau dikendalikan oleh sebuah sistem. Analisis problem
domain menghasilkan sebuah model yang merupakan gambaran dari class, objek -
objek, struktur dan perilaku (behaviour) yang ada dalam problem domain.
Gambar 2.6 Aktivitas pada problem domain modelling Sumber : Mathiassen et al. (2000, p.46)
Problem domain analysis dibagi menjadi tiga aktivitas seperti yang diperlihatkan
pada gambar 2.2 di atas. Pada problem domain analysis terdapat tiga aktivitas utama
yaitu:
1. Classes, aktivitas ini meliputi pendefinisian dan pembuatan karakteristik
problem domain dengan memilih class dan event yang menghasilkan event
table.
68
2. Structure, aktivitas ini menekankan pada penggambaran hubungan antara
class dan object yang ada pada problem domain sehingga menghasilkan class
diagram.
3. Behavior, aktivitas ini menggambarkan properti yang dinamis dan atribut-
atribut dari setiap class yang dipilih. Tujuan dari behavior adalah untuk
membuat pemodelan dinamis dari suatu problem domain.
2.9.3.1 Classes
Menurut Mathiassen et al. (2000, p.53), class merupakan deskripsi dari
kumpulan objek yang memiliki struktur, pola behaviour dan atribut yang sama. Kegiatan
kelas akan menghasilkan event table. Dimensi horizontal dari event table berisi kelas-
kelas yang terpilih, sementara dimensi vertikal berisi event-event terpilih dan tanda cek
digunakan untuk mengindikasikan objek-objek dari kelas yang berhubungan dalam event
tertentu.
Tabel 2.7 Contoh Event Table
mendaftar + +memesan * * +mengirim * * * +menagih * * + +meretur * * + +membayar * * * +
Not
a Pe
njua
lan
Sura
t Ret
ur
Buk
ti Pe
mba
yara
n
Event
Class
Pela
ngga
n
Bar
ang
Sale
s Ord
er
Sura
t Jal
an
69
2.9.3.2 Structure
Menurut Mathiassen et al. (2000, p.69) kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan
hubungan struktural antara kelas-kelas dan objek-objek pada problem domain. Ada
empat tipe hubungan struktural dimana keempatnya dibagi ke dalam dua bagian yaitu:
1. Class structure, meliputi:
a. Generalization adalah suatu kelas yang umum (kelas super) yang
menggambarkan properti umum untuk suatu grup yang memiliki kelas
khusus (sub kelas).
b. Cluster adalah suatu koleksi dari kelas yang berhubungan.
2. Object structure, meliputi:
a. Aggregation : adalah suatu objek superior (keseluruhan) yang berisi
jumlah dari objek atau bagiannya.
b. Association : adalah hubungan yang berarti antar sejumlah objek.
Hasil dari kegiatan stuktur ini adalah class diagram. Class Diagram
menghasilkan ringkasan model problem-domain yang jelas dengan menggambarkan
semua struktur hubungan statik antar kelas dan objek yang ada dalam model dari sistem
yang berubah-ubah.
2.9.3.3 Behaviour
Menurut Mathiassen et al. (2000, p.89), kegiatan ini bertujuan untuk memberi
model dinamis pada problem domain. Tugas utama dalam kegiatan ini adalah
menggambarkan pola perilaku (behaviour pattern) dan atribut dari setiap kelas. Hasil
70
dari kegiatan ini adalah statechart diagram yang dapat dilihat pada Gambar 2.7 dibawah
ini :
stm Sales
Activ e[tidak_bekerja_lagi]
/memesan
/mendaftar
Gambar 2.7 Contoh “statechart diagram”
Menurut Mathiassen (2000, p93) ada 3 notasi untuk behavioural pattern yaitu:
• Sequence, dimana event muncul satu per satu secara berurutan.
• Selection, dimana terjadi pemilihan satu event dari sekumpulan event yang
muncul.
• Iteration, dimana sebuah event muncul sebanyak nol atau beberapa kali.
2.9.4 Application Domain Analysis
Menurut Mathiassen et al. (2000,p.115), application domain adalah organisasi
yang mengatur, memonitor, atau mengendalikan problem domain. Hasil dari application
domain adalah list lengkap dari kebutuhan pengguna sistem secara keseluruhan. Gambar
2.8 di bawah ini menunjukkan aktivitas dalam application domain analysis.
71
Gambar 2.8 Aktivitas pada application-domain Sumber : Mathiassen et. al. (2000, p.115)
2.9.4.1 Usage
Menurut Mathiassen et al. (2000,p.119), kegiatan usage merupakan kegiatan
pertama dalam analisis application domain yang bertujuan untuk menentukan
bagaimana aktor-aktor berinteraksi dengan sistem yang dituju. Definisi actor itu sendiri
adalah suatu abstraksi dari pengguna atau sistem lain yang berhubungan dengan sasaran
dari sistem, sedangkan pengertian use case adalah suatu pola dari interaksi antara sistem
dan aktor dari application domain. Hasil dari analisis kegiatan usage ini adalah
deskripsi lengkap dari semua use case dan aktor yang ada digambarkan dalam tabel
aktor dan use case diagram.
72
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa usecase diagram adalah sebuah
diagram yang menggambarkan pola hubungan interaksi antara actor dan sistem, serta
menjelaskan apa saja yang actor lakukan dengan menggunakan sistem.
2.9.4.2 Function
Menurut Mathiassen et al. (2000, p.138), function adalah suatu fasilitas untuk
membuat suatu model yang berguna untuk actors. Function memfokuskan pada
bagaimana cara sebuah sistem dapat membantu aktor dalam melaksanakan pekerjaan
mereka. Function memiliki empat tipe berbeda yaitu:
a. Update, fungsi ini disebabkan oleh event problem domain dan menghasilkan
perubahan dalam state atau keadaan dari model tersebut.
b. Signal, fungsi ini disebabkan oleh perubahan keadaan atau state dari model
yang dapat menghasilkan reaksi pada konteks.
c. Read, fungsi ini disebabkan oleh kebutuhan informasi dalam pekerjaan aktor
dan mengakibatkan sistem menampilkan bagian yang berhubungan dengan
informasi dalam model.
d. Compute, fungsi ini disebabkan oleh kebutuhan informasi dalam pekerjaan
aktor dan berisi perhitungan yang melibatkan informasi yang disebabkan oleh
aktor atau model, hasil dari fungsi ini adalah tampilan dari hasil komputasi.
Tujuan dari kegiatan function adalah untuk menentukan kemampuan sistem
memproses informasi. Hasil dari kegiatan ini adalah sebuah daftar lengkap dari fungsi-
fungsi dengan spesifikasi dari fungsi yang kompleks.
73
2.9.4.3 Interfaces
Menurut Mathiassen et al. (2000, p.151), Interfaces adalah fasilitas yang
membuat suatu model dan fungsi dapat dipakai oleh aktor. Ada dua jenis interface atau
antar muka yaitu : antar muka pengguna yang menghubungkan pengguna dengan sistem
(user interface) dan antar muka sistem yang menghubungkan sistem dengan sistem yang
lainnya (system interface).
Hasil dari kegiatan ini adalah sebuah deskripsi elemen-elemen user interface dan
elemen-elemen sistem interface yang lengkap, dimana kelengkapan menunjukkan
pemenuhan kebutuhan user. Hasil ini dilengkapi dengan sebuah diagram navigasi yang
menyediakan sebuah ringkasan dari elemen-elemen user interface dan perubahan antara
elemen-elemen tersebut.
2.9.4.4 Sequence Diagram
Menurut Mathiassen et al. (2000, p340), sequence diagram menjelaskan tentang
interaksi diantara beberapa objek dalam jangka waktu tertentu. Sequence diagram
melengkapi class diagram, yang menjelaskan situasi yang umum dan statis. Sebuah
sequence diagram dapat mengumpulkan rincian situasi yang kompleks dan dinamis
melibatkan beberapa dari kebanyakan object yang digeneralisasikan dari class pada
class diagram.
Menurut Bennet et al. (2006, p252-253), sequence diagram secara semantic
ekuivalen dengan diagram komunikasi untuk interaksi yang sederhana. Sebuah sequence
diagram menunjukkan interaksi antara objek yang disusun dalam satu sequence.
74
Dalam sequence diagram yang diadaptasi dari Bennet, et al.(2006, p.252),
terdapat satu buah notasi yang disebut fragment. Fragment ini biasa digunakan dalam
setiap tipe UML diagram. Fragment yang digunakan pada sequence diagram
dimaksudkan untuk memperjelas bagaimana sequence ini saling dikombinasikan.
Fragment terdiri dari beberapa jenis interaction operator yang menspesifikasikan tipe
dari kombinasi fragment. Tipe-tipe interaction operator yang ada dalam sequence
diagram dibahas dalam Tabel 2.8 sebagai berikut:
Tabel 2.8 Tipe interaction operator yang digunakan dalam fragment Interaction Operator Penjelasan dan Penggunaan Alt Alternatives ini mewakili alternative behaviour yang ada, setiap
behaviour ditampilkan dalam operasi yang terpisah. Opt Option ini merupakan pilihan tunggal atas operasi yang hanya
akan dieksekusi bila batasan interaksi bernilai true. break Break mengindikasi bahwa dalam combined fragment
ditampilkan sementara oleh sisa dari interaction fragment yang terlampir.
Par Parallel mengindikasi bahwa eksekusi operasi dalam combined fragment biasa digabungkan dalam sequence manapun.
Seq Weak Sequencing menampilkan dalam urutan dari tiap operasi yang telah dimaintain tetapi keterjadian suatu event adalah berbeda operasinya dalam perbedaan lifeline yang dapat terjadi dalam urutan apapun.
Strict Strict Sequencing membuat sebuah strict sequence berada dalam eksekusi sebuah operasi tapi tidak termasuk urutan dalam operasi.
Neg Negative menggambarkan sebuah operasi yang bersifat invalid. Critical Critical Region mengadakan sebuah batasan dalam sebuah
operasi yang tidak memiliki event yang terjadi dalam lifeline. Ignore Ignore menandakan tipe pesan, spesifikasi sebagai parameter,
yang seharusnya diabaikan dalam sebuah interaksi. Consider Consider merupakan keadaan dimana pesan-pesan seharusnya
dipertimbangkan dalam sebuah interaksi.
75
Assert Assertion merupakan keadaan bahwa sebuah sequence dari pesanan dalam operasi hanyalah satu-satunya yang memiliki lanjutan yang bersifat sah.
Loop Loop digunakan untuk mengindikasi sebuah operasi yang diulang berkali-kali sampai batasan interaksi untuk pengulangan berakhir.
Sumber : Bennet, et al. (2006, p270)
2.9.5 Architecture Design
Menurut Mathiassen et al. (2000, p.173), tujuan dari architecture design adalah
untuk menstrukturkan sebuah sistem yang terkomputerisasi. Aktivitas-aktivitas yang
dilakukan dalam architecture design dapat dilihat pada Gambar 2.8 dibawah ini.
Gambar 2.9 Aktivitas pada architectural design Sumber : Mathiassen, et.al. (2000, p.176) 2.9.5.1 Criteria
Menurut Mathiassen et al. (2000, p.177) “tujuan dari sebuah criteria adalah
untuk mempersiapkan prioritas dari sebuah perancangan.” Sebuah perancangan yang
baik harus memperhatikan criteria-criteria seperti terlihat pada tabel 2.9 berikut ini:
76
Tabel 2.9 Tabel kriteria umum Criterion Ukuran dari
Usable Kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan konteks, organisasi yang berhubungan dengan pekerjaan dan teknis.
Secure Ukuran keamanan sistem dalam menghadapi akses yang tidak terotorisasi terhadap data dan fasilitas.
Efficient Eksploitasi ekonomis terhadap fasilitas platform teknis. Correct Pemenuhan dari kebutuhan. Reliable Pemenuhan ketepatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan
fungsi. Maintainable Biaya untuk menemukan dan memperbaiki kerusakan. Testable Biaya untuk memastikan bahwa sistem yang dibentuk dapat
melaksanakan fungsi yang dibentuk. Flexible Biaya untuk mengubah sistem yang dibentuk. Comprehensible Usaha yang diperlukan untuk mendapatkan pemahaman
terhadap sistem. Reusable Kemungkinan untuk menggunakan bagian sistem pada
sistem lain yang berhubungan. Portable Biaya untuk memindahkan sistem ke platform teknis yang
berbeda. Interoperable Biaya untuk menggabungkan sistem ke sistem yang lain.
Sumber : Mathiassen et al, 2000, p.178
Tidak ada ukuran dan cara-cara yang pasti untuk menghasilkan suatu
desain yang baik. Menurut Mathiassen et al. (2000, p.186), sebuah desain yang
baik memiliki tiga ciri-ciri yaitu :
1) Tidak memiliki kelemahan yang bersifat major
Syarat ini menyebabkan adanya pendekatan pada evaluasi dari kualitas
berdasarkan review atau eksperimen dan membantu dalam menentukan
prioritas dari kriteria yang akan mengatur dalam kegiatan desain.
77
2) Menyeimbangkan beberapa kriteria
Konflik sering terjadi antar kriteria, oleh sebab itu untuk menentukan kriteria
mana yang akan diutamakan dan bagaimana cara untuk menyeimbangkannya
dengan kriteria-kriteria yang lain bergantung pada situasi sistem tertentu.
3) Usable, flexible, dan comprehensible
Kriteria-kriteria ini bersifat universal dan digunakan pada hampir setiap
proyek pengembangan sistem.
2.9.5.2 Component Architecture
Menurut Mathiassen et al. (2000, p.189-200), arsitektur komponen adalah
sebuah struktur sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan.
Komponen sendiri merupakan kumpulan dari bagian-bagian program yang membentuk
suatu kesatuan dan memiliki fungsi yang jelas.
Beberapa pola umum dalam desain komponen arsitektur :
• Arsitektur layered
Merupakan bentuk yang paling umum dalam software. Sebuah arsitektur
layered terdiri dari beberapa komponen yang dibentuk menjadi lapisan-
lapisan dimana lapisan yang berada di atas bergantung kepada lapisan yang
ada dibawahnya. Perubahan yang terjadi pada suatu lapisan akan
mempengaruhi lapisan diatasnya. Gambar 2.10 di bawah ini menunjukkan
pola arsitektur layered.
78
Gambar 2.10 Layered Architecture Pattern Sumber : Mathiassen, et.al. (2000, p.193)
• Arsitektur generic
Pola ini digunakan untuk merinci sistem dasar yang terdiri dari antar muka,
function, dan komponen-komponen model. Dimana komponen model terletak
pada lapisan yang paling bawah, diikuti dengan function system dan
komponen interface diatasnya. Gambar 2.11 di bawah ini menunjukkan pola
arsitektur generic.
79
Gambar 2.11 Generic Architecture Pattern Sumber : Mathiassen, et.al. (2000, p.196)
• Arsitektur client-server
Pola ini awalnya dikembangkan untuk mengatasi masalah distribusi sistem di
antara beberapa processor yang tersebar secara geografis. Komponen pada
arsitektur ini adalah sebuah server dan beberapa client. Tanggung jawab
daripada server adalah untuk menyediakan database dan resources yang
dapat disebarkan kepada client melalui jaringan. Sementara client memiliki
tanggung jawab untuk menyediakan antarmuka lokal untuk setiap
penggunanya. Gambar 2.12 di bawah ini menunjukkan pola arsitektur client-
server.
80
<<component>> Client1
<<component>> Client2
<<component>> Client n
<<component>> Server
Gambar 2.12 Client-Server Architecture Pattern Sumber : Mathiassen, et.al. (2000, p.197)
Berikut adalah beberapa jenis distribusi dalam arsitektur client-server
dimana U (user interface), F (function), M (model) :
Tabel 2.10 Jenis Arsitektur client-server Client Server Architecture
U U+F+M Distributed presentation U F+M Local presentation U+F F+M Distributed functionality U+F M Centralized data U+F+M M Distributed data
Sumber : Mathiassen, et.al. (2000, p.200)
2.9.5.3 Process Architecture
Menurut Mathiassen et al. (2000, p.209-219), arsitektur proses adalah struktur
dari eksekusi sistem yang terdiri dari proses-proses yang saling tergantung. Sistem
berorientasi objek yang berjalan terdiri dari banyak sekali objek, diantaranya Active
object merupakan objek yang telah diberikan sebuah proses dan komponen program,
sebuah modul fisik dari kode program.
81
Beberapa pola distribusi dalam kegiatan desain process architecture :
1) Centralized pattern
Pada pola ini semua data ditempatkan pada server dan client hanya
menghandle user interface saja. Keseluruhan model dan semua fungsi
bergantung pada server, dan client hanya berperan seperti terminal. Gambar
2.13 mengilustrasikan pola ini.
Gambar 2.13 Deployment Diagram untuk Centralized Pattern Sumber : Mathiassen, et.al. (2000, p.216)
82
2) Distributed pattern
Pola ini merupakan kebalikan dari centralized pattern. Semua didistribusikan
kepada client dan server hanya diperlukan untuk melakukan update model
diantara clients. Gambar 2.14 mengilustrasikan pola ini.
Gambar 2.14 Deployment Diagram untuk Distributed Pattern Sumber : Mathiassen, et.al. (2000, p.217)
3) Decentralized pattern
Pola ini dapat dikatakan merupakan gabungan dari kedua pola sebelumnya.
Pada pola ini, client mengimplementasikan model yang local, sedangkan
83
server-nya memakai model common (umum).” Gambar 2.15
mengilustrasikan pola ini.
Gambar 2.15 Deployment Diagram untuk Decentralized Pattern Sumber : Mathiassen, et.al. (2000, p.219)
2.9.6 Component Design
Menurut Mathiassen et al. (2000, p.231), desain komponen bertujuan untuk
menentukan implementasi kebutuhan dalam kerangka arsitektural. Hasil dari kegiatan
ini adalah spesifikasi dari komponen yang saling berhubungan. Component design
diilustrasikan pada gambar 2.16 dibawah ini.
84
Gambar 2.16 Aktivitas pada Component Design Sumber : Mathiassen, et. al. (2000, p232)
2.9.6.1 Model Component
Menurut Mathiassen et al. (2000, p.235), Model component adalah suatu bagian
dari sistem yang mengimplementasikan problem domain. Tujuan dari komponen model
adalah untuk mengirimkan data sekarang dan historic ke function, interface dan
pengguna dan sistem yang lain.
Langkah – langkah yang harus dilakukan adalah mempresentasikan private
event, mempresentasikan common event dan restrukturisasi class. Hasil yang didapat
dalam model component adalah class diagram dari model component yang sudah
direvisi
Revisi dari class diagram dapat dilakukan dengan memperhatikan private events
dan common events. Private events adalah event yang hanya melibatkan hanya satu
object domain.
85
Tabel 2.11 Tabel Private Events Event-event yang hanya terjadi pada sequence dan selection
• Representasikan event-event ini sebagai state attribute pada class yang digambarkan oleh statechart diagram. Setiap kali ada salah satu dari events yang terlibat timbul, maka sistem akan menugaskan nilai yang baru kepada state attribute.
• Integrasikan attribute dari event yang terlibat ke dalam class.
Event-event yang terjadi berulang-ulang (iteration)
• Representasikan event-event ini sebagai suatu class baru dan hubungkan class tersebut dengan class yang dijabarkan pada statechart diagram dengan menggunakan struktur aggregation. Untuk setiap iterasi, sistem akan menghasilkan suatu object baru dari class.
• Integrasikan attribute event ke dalam class yang baru.
Jika suatu event adalah common atau umum sehingga mempengaruhi beberapa
objek, maka event tersebut perlu dihubungkan dengan salah satu objek dan dibuat
hubungan structural dengan object lain agar tetap dapat mengaksesnya.
Tabel 2.12 Tabel Common Events Common event • Jika event yang terlibat dalam statechart
diagram dalam cara yang berbeda, representasikan event tersebut dalam hubungannya ke class yang menawarkan representasikan paling sederhana
• Jika event yang terlibat dalam statechart diagram dalam cara yang sama, pertimbangkan alternatif representasi yang mungkin antara satu sama lain.
2.3.6.2 Function Architecture
Menurut Mathiassen et al. (2000, p.251), function component adalah bagian dari
sistem yang mengimplementasikan kebutuhan fungsional. Tujuan dari komponen
function adalah untuk memberikan akses bagi user interface dan komponen sistem
86
lainnya ke model, oleh karena itu function component adalah penghubung antara model
dan usage.
Hasil dari kegiatan ini adalah class diagram untuk komponen function dan
perpanjangan dari class diagram komponen model. Berikut adalah sub kegiatan dalam
perancangan komponen function dapat dilihat pada Gambar 2.16 dibawah ini:
Gambar 2.17 Sub aktivitas dalam merancang function-component Sumber : Mathiassen, et. al. (2000, p252)
Sub aktivitas ini menghasilkan kumpulan operasi yang dapat
mengimplementasikan fungsi sistem seperti yang ditentukan dalam problem domain
analysis dan function list. Berikut adalah sub kegiatan dalam component function :
1. Merancang function sebagai operation, yaitu mengidentifikasi tipe utama dari
function tersebut. Ada empat tipe function yaitu update, read, compute dan
signal
2. Menelusuri pola yang dapat membantu dalam implementasi function sebagai
operation.