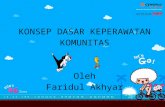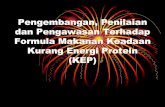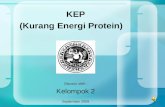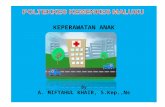Pengertian KEP
-
Upload
nur-khasanah-cilacap -
Category
Documents
-
view
1.029 -
download
1
Transcript of Pengertian KEP
PENDAHULUAN
Perbaikan keadaan gizi penting untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil, menurunkan angka kematian bayi dan balita, meningkatkan kemampuan tumbuh kembang fisik, mental dan sosial anak, dan untuk meningkatkan produktifitas kerja serta prestasi akademik. Oleh karena itu keadaan gizi merupakan salah satu ukuran penting dari kualitas sumber daya manusia. Upaya perbaikan gizi telah lama dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, melalui Departemen Kesehatan, sejak Pelita I sampai dengan Pelita VI. Upaya ini terutama diarahkan untuk menanggulangi 4 (empat) masalah gizi utama di Indonesia, yaitu : Kurang Energi Protein (KEP), Kurang Vitamin A (KVA), Anemia Gizi Besi dan Gangguan Akibat Kurang Iodium (GAKI). Khusus mengenai KEP, pada Repelita VI pemerintah bersama masyarakat berupaya menurunkan prevalensi KEP dari 40 % menjadi 30 %. Sasaran ini merupakan bukti komitmen nyata bangsa Indonesia terhadap Konvensi mengenai Hak-hak Anak tahun 1989, yang pada tahun 1997 diratifikasi oleh 191 negara anggota WHO. Dalam konvensi ini hak anak untuk mendapatkan kecukupan gizi memperoleh pengakuan penuh, dan kecukupan ini harus diperhatikan sejak dini, bahkan sejak pembuahan agar bayi bisa berkembang secara sehat dan optimal. Penyakit Kurang Energi Protein (KEP) merupakan bentuk malnutrisi yang terdapat terutama pada anak-anak di bawah umur 5 tahun dan kebanyakan di negara-negara sedang berkembang. Bentuk KEP berat memberi gambaran klinis yang khas, misalnya bentuk kwashiorkor, bentuk marasmus atau bentuk campuran kwashiorkor marasmus. Pada kenyataannya sebagian besar penyakit KEP terdapat dalam bentuk ringan. Gejala penyakit KEP ringan ini tidak jelas, hanya terlihat bahwa berat badan anak lebih rendah jika dibandingkan dengan anak seumurnya. Berdasarkan hasil penyelidikan di 254 desa di seluruh Indonesia, Tarwotjo, dkk (1978), memperkirakan bahwa 30 % atau 9 juta diantara anak-anak balita menderita gizi kurang, sedangkan 3 % atau 0,9 juta anak-anak balita menderita gizi buruk. Berbagai upaya perbaikan gizi yang selama ini dilakukan telah mampu menurunkan prevalensi KEP. Data Susenas tahun 1989, 1992, 1995 dan 1998 menunjukkan penurunan prevalensi KEP total dari 47,8% pada tahun 1989 menjadi 41,7% (1992), 35,0% (1995) dan 33,4% pada tahun 1998. Beberapa propinsi mempunyai angka KEP relatif rendah yaitu di bawah 30% (target Repelita VI), sementara di beberapa propinsi lain masih tinggi. Namun krisis ekonomi berkepanjangan yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997 menimbulkan berbagai dampak, termasuk terhadap derajat kesehatan dan keadaan gizi masyarakat berupa antara lain peningkatan jumlah penderita KEP yang ditandai dengan ditemukannya penderita gizi buruk yang selama 10 tahun terakhir sudah jarang ditemui.
PEMBAHASAN
1. Pengertian KEP Istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang diakibatkan kurangnya zat gizi terutama defisiensi protein dan energi. Arisman dalam bukunya gizi dalam daur kehidupan menyebutkan istilah lain dari KEP yaitu Kurang Kalori Protein (KKP). Serta di jelaskan bahwa KEP atau KKP ini terjadi ketika kebutuhan tubuh akan kalori, protein atau keduanya tidak tercukupi oleh diet. Pada umumnya Anak Balita merupakan kelompok umur yang paling sering menderita akibat kekurangan gizi. Hal ini disebabkan anak Balita dalam periode transisi dari makanan bayi ke makanan orang dewasa, sering kali tidak lagi begitu diperhatikan dan pengurusannya sering diserahkan
kepada orang lain, dan belum mampu mengurus dirinya sendiri dengan baik terutama dalam hal makanan. Hal ini juga di karenakan pada umur tersebut anak mengalami pertumbuhan yang pesat. Apabila konsumsi makanan tidak seimbang dengan kebutuhan kalori maka akan terjadi defisiensi tersebut (kurang kalori dan protein). Kedua bentuk defisiensi ini tidak jarang berjalan bersisian, walaupun terkadang salah satunya lebih dominan. Misalnya kekurangan kalori atau energi yang di sebut marasmus ataupun kwasiorkor karena defisiensi protein yang lebih dominan.
2. Tahap KEP
USIA LANJUT KURANG GIZI
IMR, perkembangan mental terhambat , risiko penyakit kronis pada usia dewasa Proses Pertumbuhan lambat , ASI ekslusif kurang , MP-ASI tidak benar
Kurang makan , sering terkena infeksi , pelayanan kesehatan kurang , pola asuh tidak memadai Tumbuh kembang terhambat
BBLRPelayanan Kesehatan kurang memadai Konsumsi tidak seimbang Gizi janin tidak baik
BALITA KEPKonsumsi gizi tidak cukup , pola asuh kurang
WUS KEK BUMIL KEK (KENAIKAN BB RENDAH)MMR
Pelayanan kesehatan tidak memadai
REMAJA & USIA SEKOLAH GANGGUAN PERTUMBUHANProduktivitas fisik berkurang /rendah
Konsumsi Kurang
Munculnya permasalahan gizi dapat dilihat dari ketidakseimbangan antara pejamu, agens dan lingkungan. Unsur pejamu meliputi: faktor genetis, umur, jenis kelamin, kelompok etnik, keadaan fisiologis, keadaan imunologis dan kebiasaan seseorang. Unsur sumber penyakit meliputi: faktor gizi, kimia dari luar, kimia dari dalam, faali/fisiologi, genetis, psikis, tenaga/kekuatan fisik dan biologis/ parasit. Unsur lingkungan meliputi tiga faktor yaitu lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Secara umum, konsep timbulnya penyakit dapat dibagi dalam tiga model yaitu model segi tiga epidemiologi, model jaring-jaring sebab akibat dan model roda. Model segi tiga epidemiologi yaitu kualitas antara pejamu, sumber penyakit, dan lingkungan. Menurut model ini, perubahan salah satu faktor akan merubah ke-seimbangan antara ketiga unsur tersebut. Menurut model jaring-jaring sebab akibat, suatu penyakit tidak tergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses "sebab akibat". Menurut model roda, suatu penyakit disebabkan oleh hubungan antara manusia
dengan lingkungan hidupnya. Proses riwayat alamiah terjadinya penyakit yang diterapkan pada masalah gizi (gizi kurang) melalui berbagai tahap yaitu diawali dengan terjadinya mteraksi antara pejamu, sumber penyakit dan lingkungan. Ketidakseimbangan antara ketiga faktor ini, misalnya terjadinya ketidakcukupan zat gizi dalam tubuh maka, sim-panan zat gizi akan berkurang dan lama kelamaan simpanan menjadi habis. Apabila keadaan ini dibiarkan maka akan terjadi perubahan faali dan metabolis, dan akhirnya memasuki ambang klinis. Proses itu berlanjut sehingga menyebabkan orang sakit. Tingkat kesakitannya dimulai dari sakit ringan sampai sakit tingkat berat. Dari kondisi ini akhirnya ada empat kemungkinan yaitu mati, sakit kronis, cacat dan sembuh apabila ditanggulangi secara intensif. Patogenesis penyakit gizi kurang melalui 5 tahapan yaitu: pertama, ketidakcukupan zat gizi. Apabila ketidakcukupan zat gizi ini berlangsung lama maka persediaan cadangan jaringan akan digunakan untuk memenuhi ketidakcukupan itu. Kedua, apabila ini berlangsung lama, maka akan terjadi kemerosotan jaringan, yang ditandai dengan penurunan berat badan. Ketiga, terjadi perubahan biokimia yang dapat dideteksi dengan pemeriksaan laboratorium. Keempat, terjadi perubahan fungsi yang ditandai dengan tanda yang khas. Kelima, terjadi perubahan anato-mi yang dapat dilihat dari munculnya tanda yang klasik. Kurang energi protein dapat dikelompokan dalam 2 kelompok yaitu kelompok primer dan sekunder, kelompok primer disebabkan karena ketiadaan pangan sehingga asupan pangan ke dalam tubuh kurang. Sedangkan kategori sekunder disebabkan oleh penyakit yang mengakibatkan kurangnya asupan, gangguan penyerapan dan untilitas pangan serta peningkatan kebutuhan zat gizi. 3. Jenis KEP Pada umumnya KEP terdiri dari tiga bentuk yaitu : a) Marasmus Marasmus merupakan defisiensi intake energi yang umumnya terjadi pada anak-anak sebelum usia 18 bulan karena terlambat diberi makanan tambahan. Kata marasmus berasal dari bahasa yunani yang artinya kurus kering. Marasmus terjadi karena penyapihan mendadak, formula pengganti ASI yang terlalu encer dan tidak
higienis atau sering terkena infeksi terutama gastroenteritis. Marasmus berpengaruh jangkla panjang terhadap mental dan fisik serta sulit diperbaiki. Marasmus disebabkan karena kurang kalori yang berlebihan, sehingga membuat cadangan makanan yang tersimpan dalam tubuh terpaksa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup. Penyakit kelaparan ini banyak terjadi pada kondisi sosial ekonomi rendah di negara berkembang. Patofisiologi Dalam keadaan kekurangan makanan, tubuh selalu berusaha untuk mempertahankan hidup dengan memenuhi kebutuhan pokok atau energi. Kemampuan tubuh untuk mempergunakan karbohidrat, protein dan lemak merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan; karbohidrat (glukosa) dapat dipakai oleh seluruh jaringan tubuh sebagai bahan bakar, sayangnya kemampuan tubuh untuk menyimpan karbohidrat sangat sedikit, sehingga setelah 25 jam sudah dapat terjadi kekurangan. Akibatnya katabolisme protein terjadi setelah beberapa jam dengan menghasilkan asam amino yang segera diubah jadi karbohidrat di hepar dan di ginjal. Selama puasa jaringan lemak dipecah jadi asam lemak, gliserol dan keton bodies. Otot dapat mempergunakan asam lemak dan keton bodies sebagai sumber energi kalau kekurangan makanan ini berjalan menahun. Tubuh akan mempertahankan diri jangan sampai memecah protein lagi setelah kira-kira kehilangan separuh dari tubuh. Tanda-tanda yang sering dijumpai pada pada penderita marasmus yaitu :
Sangat kurus, tinggal tulang terbungkus kulit bahkan sampai berat badan dibawah waktu lahir. Wajahnya seperti orang tua Kulit keriput, pantat kosong, paha kosong, tangan kurus dan iga nampak jelas. Gejala marasmus adalah seperti gejala kurang gizi pada umumnya (seperti
lemah lesu, apatis, cengeng, dan lain-lain), tetapi karena semua zat gizi dalam keadaan kekurangan, maka anak tersebut menjadi kurus-kering. Jumlah anak balita gizi buruk di Indonesia, menurut laporan UNICEF tahun 2006, menjadi 2,3 juta jiwa. Ini berarti naik
sekitar 500.000 jiwa dibandingkan dengan data tahun 2004/2005 sejumlah 1,8 juta jiwa . Penyakit penyerta Penyakit penyerta yang sering dijumpai adalah enteritis, infestasi cacing, tuberkolosis, dan defisiensi vitamin A. Karena itu pada pemeriksaan anak dengan marasmus hendaknya diperhatikan kemungkinan adanya peyakit tersebut, yang akan mempengaruhi tindakan pengobatan. b) Kwarsiorkor Kata kwarshiorkor berasal dari bahasa Ghana-Afrika yang berati anak yang kekurangan kasih sayang ibu. Kwashiorkor adalah salah satu bentuk malnutrisi protein berat yang disebabkan oleh intake protein yang inadekuat dengan intake karbohidrat yang normal atau tinggi. Agar tercapai keseimbangan nitrogen yang positif, bayi dan anak dalam masa pertumbuhan memerlukan protein lebih banyak diandingkan dengan orang dewasa. Keseimbangan nitrogen yang positif pada orang dewasa tidak diperlukan, karena kebutuhan protein sudah terpenuhi bila keseimbangan tersebut dapat dipertahankan. Pada anak bila keseimbangan nitrogen yang positif tidak terpenuhi, maka setelah beberapa saat akan menderita malnutrisi protein yang mungkin berlanjut dengan kwashiorkor. Meskipun sebab utama penyakit ini adalah defisiensi protein, tetapi karena bahan makanan yang dimakan kurang mengandung nutrien lainnya ditambah dengan konsumsi setempat yang berlainan, maka akan terdapat perbedaan gambaran kwashiorkor di berbagai Negara. Umumnya defisiensi protein disertai pula oleh defisiensi energi, sehingga pada seorang kasus terdapat gejala kwashiorkor maupun marasmus. Patofisiologi Pada defisiensi protein murni tidak terjadi katabolisme jaringan yang sangat berlebih, karena persediaan energi yang dipenuhi oleh jumlah kalori dalam dietnya. Kelainan yang mencolok adalah gangguan metabolic dan perubahan sel yang
menyebabkan edema dan perlemakan hati. Karena kekurangan protein dalam diet, akan terjadi kekuranganberbagai asam amino esensial dalam serum yang diperlukan untuk sintesis dan metabolisme. Selama diet mengandung cukup karbohidrat, maka produksi insulin akan meningkat dan sebahagian asam amino dalam serum ini akan menyebabkan kurangnya produksi albumin oleh hepar, yang kemudian berakibat timbulnya edema. Perlemakan hati terjadi karena gangguan pembentukan betalipoprotein, sehingga transport lemak dari hati ke depot terganggu, dengan akiatnya terjadinya penimbunan lemak dalam hati.. Penyakit yang sering terdapat bersamaan kwarsiorkor adalah defisiensi vitamin A, infestasi cacing, tuberkolosis bronkopneumonia dan noma.
Kurang makan
Penurunan kadar cadangan zat gizi dalam tubuh
Penurunan kadar zt gizi dalam cairan tubuh
Penurunan fungsi jaringan
Penurunan fungsi enzim terkait zat gizi
Perubahan fungsi
Perubahan klinis
Perubahan anatomi Gibson(1990)
Epidemiologi Kasus ini sering dijumpai di daerah miskin, persediaan makanan yang terbatas, dan tingkat pendidikan yang rendah. Penyakit ini menjadi masalah di negara-negara miskin dan berkembang di Afrika, Amerika Tengah, Amerika Selatan dan Asia Selatan. Di negara maju sepeti Amerika Serikat kwashiorkor merupakan kasus yang langka. Berdasarkan SUSENAS (2002), 26% balita di Indonesia menderita gizi kurang dan 8% balita menderita gizi buruk (marasmus, kwashiorkor, marasmus-kuarsiorkor). Tanda-tanda Tanda-tanda yang sering dijumpai pada pada penderita Kwashiorkor yaitu :
Gagal untuk menambah berat badan wajah membulat dan sembap Rambut pirang, kusam, dan mudah dicabut Pertumbuhan linear terhenti Endema general (muka sembab, punggung kaki, dan perut yang membuncit). Diare yang tidak membaik Dermatitis perubahan pigmen kulit Perubahan warna rambut yang menjadi kemerahan dan mudah dicabut Penurunan masa otot Perubahan mentak seperti lathergia, iritabilitas dan apatis yang terjadi Perlemakan hati, gangguan fungsi ginjal, dan anemia
Pada keadaan akhir (final stage) dapat menyebabkan shok berat, coma dan
berakhir dengan kematian. Cara mengatasi kwarshiorkor Dalam mengatasi kwashiorkor ini secara klinis adalah dengan memberikan makanan bergizi secara bertahap. Contohnya : Bila bayi menderita kwashiorkor, maka bayi tersebut diberi susu yang diencerkan. Secara bertahap keenceran susu dikurangi, sehingga suatu saat mencapai konsistensi yang normal seperti susu biasa kembali. Fakta terjadinya kwarshiorkor Bandung, Kompas - Sedikitnya 95 anak balita di 10 kabupaten/kota di Jawa Barat menderita busung lapar, dua anak balita kwashiorkor dan satu anak balita menderita komplikasi busung lapar kwashiorkor .Angka itu diperkirakan hanya angka awal dari fenomena gunung es karena seluruhnya ada 25 kabupaten/kota. Diduga jumlah ini sekitar 50 persen dari jumlah keseluruhan penderita sebab belum semua ibu melaporkan kondisi anaknya yang kurang gizi karena kendala jarak ke pos pelayanan kesehatan setempat atau karena tidak bisa meninggalkan pekerjaan. c) Marasmik-kwarsiorkor Gambaran dua jenis gambaran penyakit gizi yang sangat penting. Dimana ada sejumlah anak yang menunjukkan keadaan mirip dengan marasmus yang di tandai dengan adanya odema, menurunnya kadar protein (Albumin dalam darah), kulit mengering dan kusam serta otot menjadi lemah. Adalah infeksi saluran nafas atas, bronkopneumonia, koch pulmonum, nomaotitis, mediasukurativa, infeksi saluran kemih, penyakit parasit dan diare. Tidak jarang penyakit penyerta ini menjadi penyebab utama marasmik kwarsiorkor, misalnya diare menahun atau tuberkolosis. Oleh karena itu penyakit penyerta itu harus diobati secara tunas Menurut Dr. Magdalena, sampai 28 Mei 2005 jumlah gizi buruk dari Kabupaten/Kota P. Lombok berjumlah 559 kasus termasuk 51 kasus yang dirawat di RSU Mataram. Diantara kasus gizi buruk tersebut 8 anak diantaranya meninggal dunia. Kasus gizi buruk tersebut masing-masing tersebar di Kota Mataram sebanyak 23 kasus ( 2 diantaranya meninggal), Kab. Lombok Barat 133 kasus ( 5 diantaranya meninggal dunia), Kab. Lombok Tengah 25 kasus ( 1 diantaranya meninggal dunia) dan Kab.
Lombok Timur 178 kasus. Dari kasus gizi buruk tersebut, tergolong gizi buruk dengan gejala klinis yaitu Marasmus 16 kasus, Kwashiorkor 1 kasus dan Marasmus + Kwashiorkor 4 kasus. 4. Macam- macam klasifikasi KEP a) Klasifikasi KEP menurut Gomez Gomez(1956) mengklasifikasikan KEP berdasarkan berat badan terhadap usia, berat badan anak yang diperikasa dinyatakan sebagai persentase dari berat anak sesusia yang diharapkan sesuai dengan baku acuan dengan menggunakan persentil ke 50 baku acuan harvard Kalori (derajat KEP) 0 = Normal 1 = Ringan 2 = Sedang 3 = Berat BB/U(%) 90 % 89-75% 74-60% < 60%
Pengelompokan KEP menurut Gomez ini sangat bermanfaat dalam penelitian epidemiologis dan kesehatan masyarakat karena proporsi anak di masyarakat yang pada suatu ketika dalam hidupnya pernah mengalami KEP dapat ditentukan. Namun dalam pengelompokan ini tidak dapat dilihat perbedaan antara marasmus dengan kwarsiorkor. Akibatnya anak yang rasio berat badanya rendah terhadap usia sangat rendah tidak termasuk penderita KEP karena anak yang kurus ini memiliki ukuran tinggi badan yang rendah pula. b) Klasifikasi menurut Waterlow Klasifikasi menurut waterlow menggunakan indikator berat badan terhadap usia dan berat badan. Klasifikasi ini masih mengacu pada acuan baku harvard. Kategori Stunting (Tinggi menurut umur) Wasting (Berat menurut tinggi)
0 1 2 3
>95% 95-90% 89-85% 85%
>90% 90-80% 80-70%