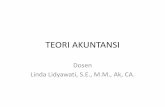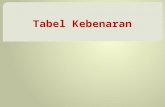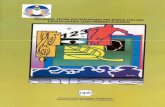TEORI KEBENARAN MURTAḌÁ MUṬAHARĪ (Mengkaji ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of TEORI KEBENARAN MURTAḌÁ MUṬAHARĪ (Mengkaji ...
TEORI KEBENARAN MURTAḌÁ MUṬAHARĪ
(Mengkaji Konsep dan Kritiknya terhadap Barat)
Diajukan kepada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan Ujian Tesis
Disusun Oleh
HAIRUS SALEH
NIM : 21151200100045
Dosen Pembimbing:
Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A
PROGRAM MAGISTER PENGKAJIAN ISLAM
KONSENTRASI PEMIKIRAN ISLAM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2020
i
KATA PENGANTAR
Rasa syukur yang amat sangat mendalam, penulis haturkan kepada Allah
SWT atas segala rahmat dan petunjuk-Nya maka tesis dengan judul “Teori
Kebenaran menurut Murtaḍá Muṭahharī” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam
senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dalam kesempatan ini
penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Abdul
Mu’im dan ibunda tercinta Hamidah dan Darmasiah, Istri Shofiatul Jannah yang
selalu memberikan motivasi kepada penulis serta anak saya Syahida Humaira Khair
yang selalu membuat semangat.
Penulisan tesis ini pada dasarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam memperoleh gelar Magister Pemikiran Islam pada Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagaimana manusia
yang tidak luput dari penulisan tesis ini merupakan suatu respons terhadap
banyaknya pendapat yang membahas teori kebenaran baik dari Barat hingga Islam.
Sehingga dari perdebatan-perdebatan mengenai kebenaran tersebut, penulis ingin
mengkaji lebih mendalam tentang kebenaran menurut Murtaḍá Muṭahharī dalam
teori kebenarannya yang komprehensif.
Tentunya, proses penulisan tesis ini tentunya melibatkan banyak kalangan,
untuk itu kami merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu menyelesaikan skripsi ini, terutama penulis sampaikan kepada:
1. Segenap civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Prof. Dr. Amani
Lubis (Rektor UIN Jakarta), Prof. Dr. Jamhari, M.A. (Direktur Sekolah
Pascasarjana UIN Jakarta), Arif Zamhari, M.Ag., Ph.D. (Ketua Jurusan
Magister Pengkajian Islam Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta).
2. Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A. sebagai pembimbing, mengayomi, dan
memberikan ide dan gagasan yang konstruktif dalam penyelesaian tesis ini.
3. KH. Holilur Rahman dan keluarga, serta KH. Fauzi Tijani dan keluarga yang
telah banyak membantu dalam proses penyelesaian studi.
4. Pimpinan dan segenap civitas akademika SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
yang telah banyak membantu kelancaran administrasi dan birokrasi.
5. Teman-teman seperjuangan di sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, Mohammad Firdaus, Helmi Hidayatullah, Moh. Robith Rosfan yang
telah berbagi ilmu, keceriaan, dan berbagi kisah dengan penulis.
6. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga
kebaikan selalu bersama kita semua.
Pada akhir pengantar ini, penulis mengharapkan saran dan masukan dari
para pembaca agar karya ini lebih baik lagi. Semoga karya ini memberi kontribusi
positif terhadap perkembangan filsafat Islam.
Jakarta, 29 Desember 2019
Hairus Saleh
vii
ABSTRAK
Kebenaran merupakan kesesuaian antara “pembawa kebenaran” dengan
realitas sebagaimana adanya. Realitas bisa berupa objek materi, rasional maupun
intuitif. Setiap kebenaran mempunyai ranahnya masing-masing. Kebenaran intuitif
didapat melalui hati, ia tak dapat diukur oleh teori-teori empiris, begitu juga
sebaliknya. Namun antara berbagai kebenaran tersebut tidak dapat dipertentangkan.
Justru di antara tiga kebenaran tersebut terjadi saling berhubungan dan saling
menguatkan.
Temuan penelitian ini mengkonfirmasi temuan penelitian Mulyadi
Kartanegara, Imron Mustofa yang menyatakan bahwa kebenaran merupakan
kesesuaian antara “pembawa kebenaran” dengan realitas, berupa realitas fisik dan
realitas nonfisik. Kebenaran fisik harus diukur dengan materi, kebenaran nonfisik
diukur menggunakan kaidah-kaidah logika jika berkaitan dengan logika dan diukur
oleh pengalaman batin jika karakteristik objeknya adalah realitas metafisik.
Temuan penelitian ini berbeda dengan temuan penelitian Achmad Charris
Zubair yang mengatakan kebenaran merupakan kesesuaian dengan realitas,
kesesuaian dengan kaidah-kaidah logika dan mempunyai manfaat. Juga sekaligus
membantah apa yang ditemukan oleh Saifuddin bahwa dalam menentukan
kebenaran antara filsafat dan agama terdapat perbedaan. Sedangkan Murtaḍá justru
menjadikan al-Qur’an sebagai dasar pemikirannya.
Metode yang digunakan dilihat dari tujuan penyelenggaraan penelitian ini
ialah deskriptif analitik. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk
mengkaji lebih detail tentang suatu gejala. Sedangkan pendekatan yang digunakan
ialah pendekatan filosofis.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami teori kebenaran menurut
Murtaḍá Muṭahharī dan untuk mengetahui bagaimana cara mencapai kebenaran
Murtaḍá Muṭahharī. Secara praktis, penelitian ini akan mempermudah dan
memperjelas pemahaman masyarakat terhadap pemikiran Murtaḍá Muṭahharī
tentang kebenaran. Sedangkan manfaat akademik penelitian ini ialah memperkaya
khazanah kajian-kajian akademik.
Kata Kunci: teori kebenaran, kebenaran intuitif, kebenaran empiris, kebenaran
rasional.
viii
م ل خ م الر ل ال ة
منح جاء با مع الحواقع قيقة هي تطابق ب يح كانه أنح يكون كائنا ماديا، أوح .املوجودالح الحواقع بإمحسيا لنيا أوح حدح قيقة ا ا ا ع حدد ة ك ل و . عقح سيدة بعم يدة الحق حب، ول ي تأتد .الح دح قيقة الح تسب الح تكح
يح ح ت ة . قياس ا بالند ياا التد ح يييدة، والحعكح قائق الحم ح الح .ولكند، ل ت ل أنح تكوحن الحمعار ة ب يحقائق اللدل . م حتيطح ب عحض ا بي عحضة وي عزز ب عحض ا ب عحضا ب ح ك ل ه الح
ا الحياحث ث الندتائج الدت و إلي ح غل رل ت ؤكد ن تائج ه ا الحي ح ، عمل ن مصطلفلى و موايل دةي كل رتل نةي منح جاء با مع الحواقع فعحل، إمدا أنح يكوحن الحواقع ماديا قة هي عيار ح عن التدطابق ب يح قي ح الد ان دحا بأند الح
ماد ي دام .و إمدا ي ح ت ح الحماديدة يتمل قياس ا باسح قيقة ي ح قة الحماديدة يب أنح ت قاس بالحمادد ، أمدا الح قي ح الحق واعد الحمنحطق إذا كانتح م حتيطة بالحمنحطق ويتمل قياس ا بالتد ح بة الحياطنيدة إذا كانتح خ ائص الحموح وع هي
.(ميتافيزيقيدةح )حقيقةح يحييدةح ث لححد ث عنح ن تائج الحي ح قيقة هي التدطابق رحاتحت ف ن تائج ه ا الحي ح زب يح الد ح قال أند الح
اومع الحواقع والت دوافق مع ق واعد الحمنحطق ت اد من ح ث ن ما . إمحكان الحسح سيحف ق در كما أند ه ا الحي حين يحن ف تحديحدهاحيحث الد الد الح حس ة و ب يح قيقة محت فح ب يح نما كان . قال أند الح يحع الحق حآن ملتلضلىب ي ح
ته .أساسا ل كحتنادا ي ي اسح ي التد ح ث ع أسح وح الحو ح ث، تسي ط يقة ه ا الحي ح يل . د الحي ح ث الحو ح الحي ح
ج الح حس يد ث الحمن ح دم الحي ح ت ح اراا الحمعح و ة، كما يسح ي حوحل ااح راسة بالت د ح .هو الدقة منح ج ة ن قي ح ومعح فة كيح يدة الحو ول ملتلضلى مطخهخلةيهد ه ال سالة هو ف مح ن يدة الح
قيقة عا منح . انيه إل الح تي ح تمع و الت دوح ي مح ف الحسح يح الحم ح ع إل تسح ث يسح ت ارة، ه ا الحي ح وباخح قيقة ملتلضلى مطخهخلةيفكح اما ل . عن الح ث ي عحتي إسح زانة أمدا منح حيحث الح وائد الحع حميدة فإند ه ا الحي ح
.الحي وح الحع حميدة ساسيدة لنيدة : الحعياراا الح قيقة الحعقح قيقة التد ح يييدة، الح سيدة، الح دح قة الح قي ح قة، الح قي ح .ن يدة الح
ix
ABSTRACT
Truth is a conformity between "truth bearer" and reality as it is. Reality can
be a material object, rational or intuitive. Every truth has its own realm. Intuitive
truth is obtained through heart, it cannot be measured by empirical theories, and vice
versa. However, various truths cannot be contested. In fact, the three truths are
interconnected and mutually reinforcing.
The findings of this study confirm the research findings by Mulyadi
Kartanegara, Imron Mustofa, stating that truth is a match between "truth bearer"
with reality, in the form of physical reality and non-physical reality. Physical truth
must be measured by matter, non-physical truth is measured using the rules of logic
if it is related to logic and measured by inner experience if the characteristics of the
object are metaphysical reality.
The findings of this study are different from the findings of Achmad Charris
Zubair's research stating that truth is conformity with reality, conformity with the
rules of logic, and having benefits. This research findings, at the same time, also
deny what was found by Saifuddin that there were differences in determining the
truth between philosophy and religion. Whereas, Murtaḍá actually makes the Qur'an
as the basis of his thought.
The method used in this study was analytic descriptive. Descriptive research
is research conducted to examine in more detail about a symptom. The approach
used was a philosophical approach.
This research aims to comprehend the truth theory according to Murtaḍá
Muṭahharī and to find out how to achieve the truth of Murtaḍá Muṭahharī.
Practically, this research will facilitate and clarify people's understanding of
Murtaḍá Muṭahharī's thoughts about truth. While academically, this research aims to
enrich the treasury of academic studies.
Keywords: theory of truth, intuitive truth, empirical truth, rational truth.
xi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................... i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ........................................................ ii
LEMBAR PENGECEKAN PLAGIARISME ................................................. iii
LEMBAR PERNYATAAN PERBAIKAN ........................................................ iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................................... v
PERSETUJUAN HASIL UJIAN TESIS ........................................................... vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA ................................................................. vii
ABSTRAK BAHASA ARAB .......................................................................... viii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS ....................................................................... ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ......................................................................... x
DAFTAR ISI ........................................................................................................ xi
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah .................................................................................. 1
B. Identifikasi Masalah ...................................................................................... 11
C. Rumusan Masalah .......................................................................................... 11
D. Batasan Masalah ............................................................................................ 11
E. Tujuan Penelitian ........................................................................................... 11
F. Manfaat Penelitian ......................................................................................... 12
G. Kajian Pustaka ............................................................................................... 12
H. Metodologi Penelitian ..................................................................................... 15
I. Sistematika Pembahasan ................................................................................ 16
BAB II TEORI KEBENARAN DARI BERBAGAI PANDANGAN ............. 19
A. Model-model Kebenaran ............................................................................... 19
B. Berbagai Macam Teori Kebenaran ................................................................ 27
C. Pandangan Islam tentang Kebenaran ............................................................. 36
D. Pandangan Barat tentang Kebenaran ............................................................. 45
BAB III LATAR BELAKANG MURTAḌÁ MUṬAHARĪ ............................ 53
A. Biografi .......................................................................................................... 53
B. Latar belakang Pemikiran dan Karyanya ....................................................... 58
C. Peran Murtaḍá Muṭahharī dalam Pemikiran Islam ........................................ 65
BAB IV KONSTRUKSI TEORI KEBENARAN MURTAḌÁ MUṬAHARĪ ....
A. Pandangan tentang Kebenaran ....................................................................... 69
xii
1. Pandangan Murtaḍá Muṭahharī tentang Korespondensi, Koherensi ....... 69
2. Persoalan Pembawa Kebenaran .............................................................. 73
3. Pandangan Murtaḍá tentang Fakta .......................................................... 74
4. Sumber-sumber Kebenaran ..................................................................... 76
B. Berbagai Model Kebenaran dan Ruang Lingkupnya ..................................... 78
1. Kebenaran Materi .................................................................................... 78
2. Kebenaran Logis ..................................................................................... 80
3. Kebenaran Intuitif ................................................................................... 81
C. Metode Pembuktian Kebenaran ..................................................................... 83
1. Metode Eksperimen ................................................................................ 83
2. Metode Koherensi ................................................................................... 85
3. Metode Pengalaman Batin ...................................................................... 86
D. Kebenaran dan Fitrah Manusia ...................................................................... 87
1. Hubungan Kebenaran dengan Kesucian Jiwa ......................................... 87
2. Hal-hal yang Menghalangi Seseorang terhadap Kebenaran ................... 88
BAB V KRITIK MURTAḌÁ MUṬAHARĪ TERHADAP BARAT .............. 91
A. Kritik Murtaḍá Muṭahharī terhadap Teori Kebenaran Karl Marx ................. 91
B. Kritik Murtaḍá Muṭahharī terhadap Teori Kebenaran René Descartes .......... 96
C. Kritik Murtaḍá Muṭahharī terhadap Teori Kebenaran Auguste Comte ....... 100
BAB VI PENUTUP .......................................................................................... 107
A. Kesimpulan .................................................................................................. 107
B. Kritik dan Saran ........................................................................................... 108
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 109
GLOSARI ......................................................................................................... 120
INDEKS ............................................................................................................ 121
BIODATA ......................................................................................................... 123
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kebenaran pada dasarnya merupakan fitrah bagi setiap manusia. Manusia
dikatakan oleh Murtaḍá Muṭahharī sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu
mencari kebenaran.1 Pencarian kebenaran bagi manusia merupakan pembeda dari
hewan. Dalam tiap hidupnya manusia terus mencintai kebenaran. Manusia setiap
saat selalu mendambakan kebenaran, bahkan menurut Fahruddin Faiz dalam diri
manusia sebenarnya telah tertanam kebenaran. Maka tidak heran jika kemudian
dalam setiap langkah manusia selalu dimotivasi oleh pencarian akan kebenaran.
Peperangan yang terjadi antara Islam dan Kristen beberapa abad lalu juga
dilandaskan pada keyakinan akan kebenaran ajaran agamanya masing-masing.
Bahkan dalam setiap individu mempunyai kepercayaan akan kebenaran berdasarkan
pengalaman sendiri.2 Misalkan satu individu mengatakan bahwa sate sangat enak,
sedangkan yang lainnya mengatakan tidak enak. Keduanya sama-sama benar
berdasarkan kesukaan masing-masing. Namun jika setiap orang mempunyai
kebenaran yang berbeda pada setiap individu, lalu kebenaran yang mana yang
hendak dijadikan patokan?
Istilah “kebenaran” dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret
maupun abstrak. Truth adalah sebutan kebenaran dalam bahasa Inggris. Varitas
(bahasa Latin) dan eletheid (bahasa Yunani) merupakan lawan kata dari kesalahan,
kesesatan, kepalsuan dan terkadang juga opini.3 Kebenaran dapat juga disebut
sebagai al-ḥaq (bahasa Arab) yang mengandung arti Naqid al-bāṭil. Naqid al- bāṭil yang mengandung arti lawan dari yang rusak, sesat, salah atau batal.
4 Dalam kamus
bahasa Indonesia, kata kebenaran diartikan sebagai sebuah kata yang menunjukkan
kepada sebuah keadaan yang cocok dengan yang sesungguhnya. Dalam arti suatu
keadaan yang benar-benar ada.5 Abbas Hamami mengatakan bahwa jika seseorang
menuturkan kebenaran, yang dimaksud ialah berupa proposisi yang benar. Proposisi
maksudnya adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement.
Jika seseorang menyatakan kebenaran bahwa proposisi yang diuji pasti memiliki
kualitas, sifat atau karakteristik, hubungan dan nilai, maka hal yang demikian itu
karena kebenaran tidak dapat begitu saja terlepas dari kualitas, sifat, hubungan dan
nilai itu sendiri.
Joachim memahami kebenaran bukan berdasarkan kesesuaian suatu hal
dengan fakta, melainkan keselarasan dengan berbagai pengetahuan yang sudah ada
1 Nur Idam Laksono, “Tasawuf Untuk Kemanusiaan : Kajian Terhadap Konsep
Fitrah Murtaḍá Muṭahharī”, dalam Attanwir, v. 05, n0. 02, September 2015, h. 23. 2 Jujun S. Suriasumantri, Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan
tentang Hakikat Ilmu, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 10. 3 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 412.
4 Ibnu Manzhur, Lisān al-‘ Arab, (Beirut: Dār Shādir, 1412/1992), Jilid 10, h. 49-
58. 5 Tim Penyusun Kamus PPPB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai
Pustaka, 1994), h. 114.
2
sebelumnya. “Truth in its essential nature is that systematic coherence with is the
character of a significant whole.”6 Teori ini mengisyaratkan kebenaran koheren di
mana suatu kebenaran dari pembawa kebenaran7 diukur berdasarkan hubungan-
hubungan pembawa kebenaran dengan pembawa kebenaran lain yang sebelumnya
sudah teruji kebenarannya. Pandangan berbeda dengan pandangan para pragmatisme
yang menilai kebenaran sebagai sebuah hasil yang memuaskan keinginan dan tujuan
manusia. Kebenaran dalam versi koherensi dapat disajikan dengan saling
keterhubungan yang sistematik, konsistensi, selaras, serta kecocokan antara suatu
pernyataan dengan lainnya yang lebih dahulu diakui, diterima, dan diketahui
kebenarannya. Loren Bagus mengatakan bahwa dasar kebenaran adalah yang ada
atau eksistensi.8 Kebenaran dapat ditemukan dengan beberapa cara di antaranya
ialah oleh akal sehat, intuitif, trial and error, otoritas, prasangka dan wahyu.
Dari beberapa pandangan yang telah dibahas tadi, ditemukan term yang
sering kali digunakan dalam menjelaskan makna dari kebenaran; di antaranya ialah;
compatibility, objective process, coherence with significant whole, practical effect,
dan correspondence. Dari situlah dapat kita katakan bahwa kebenaran adalah
persesuaian antara realitas dan teori yang dapat dibuktikan secara objektif, dapat
diterima oleh banyak orang serta dapat memiliki manfaat praktis.
Kebenaran yang berkaitan dengan intelektual dan realitas dibagi menjadi
tiga9 yaitu pertama kebenaran berkaitan dengan etika. Kebenaran dalam tataran ini
menunjukkan hubungan antara hal yang dikatakan dengan hal yang dirasakan atau
dipikirkan. Kedua kebenaran yang berkaitan dengan logika. Kebenaran dalam
tataran ini menunjukkan hubungan antara keputusan dan realitas objektif. Kebenaran
ini berkaitan dengan logika, epistemologi dan psikologi. Ketiga adalah kebenaran
yang berkaitan dengan yang ada, yaitu dalam tingkat ontologis.
Perdebatan tentang kebenaran tampaknya sudah terjadi sejak zaman Yunani
kuno. Perdebatan itu kemudian merambah kepada pemikiran selanjutnya. Kajian
tentang teori kebenaran dalam kajian filsafat dan lainnya terus mengalami
perdebatan yang menarik. Dalam Islam sendiri pun terdapat dinamika itu. Ada yang
mengatakan kebenaran dapat dicapai menggunakan rasio, indera, hati dan lainnya.
Masing-masing mempunyai pendapat dan argumen yang berbeda, tidak terkecuali
Murtaḍá Muṭahharī. Ia menyajikan teori kebenaran yang cukup menarik. Ia pun
mengajukan kritik-kritiknya kepada filosof Islam maupun Barat seperti Plato.
Di antara yang menarik lainnya dari pembahasan tentang teori kebenaran
menurut Murtaḍá ialah bahwa tulisan-tulisannya termasuk juga tulisan tentang teori
kebenaran merupakan bentuk refleksi dari berbagai kegelisahan intelektual dan
merupakan reaksi terhadap dinamika sosial yang terjadi pada saat ia hidup. Pada
6 Peter Brophy, Narrative-based Practice, (New York: Rutledge, 2016), h. 72.
7 Pembawa kebenaran ialah hal-hal yang bisa mempunyai nilai kebenaran, yaitu hal
macam apa yang bisa benar atau salah. Di antaranya ialah keyakinan, proposisi, penilaian,
laporan teori, pernyataan, gagasan, kegiatan pikiran, ucapan. Richard L. Kirkham, Theories
of Truth, (Cambridge, Massachusetts Institute of Technology Press (MIT Press), 1992), h.
54. 8 Lorens Bagus, Kamus Filsafat ..., h. 86.
9 Suparlan Suhartono, Filsafat Ilmu Pengetahuan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,
2008), h. 93-95.
3
masa Murtaḍá hidup di Iran, partai Tudeh (partai komunis Iran) kerap kali
menyebarkan berbagai propaganda untuk mempengaruhi masyarakat Islam Iran agar
menjadikan materialisme sebagai ideologi dan landasan hidup.10
Terbukti pada
waktu itu, anak-anak muda Iran mulai menerimanya sebagai kebenaran, dan
menganggap ajaran Islam tidak relevan lagi dengan zaman.
Melihat kenyataan tersebut, Murtaḍá kemudian melancarkan kritik-kritik
tajam dalam rangka mengembalikan pemahaman masyarakat yang menurutnya telah
melalui jalan yang sesat sebagaimana kesesatan para materialisme. Salah satu tokoh
Barat yang dikritik ialah Karl Marx, Plato, Descartes, Auguste Comte dan lainnya.
Sebelum Plato sebenarnya sudah terjadi pembahasan tentang kebenaran di
masyarakat Yunani kuno. Kajian kebenaran itu dimulai oleh kaum Sofis, dengan
mengatakan bahwa kebenaran adalah relatif. Kebenaran dapat diciptakan oleh
permainan retorika. Sedangkan retorika sebenarnya tidak peduli terhadap kebenaran
hakiki.11
Maka kebenaran bagi kaum sofis hanya sebatas dalam retorika. Satu
kebenaran akan berubah menjadi salah dalam waktu yang berbeda ketika dibantah
oleh kalimat-kalimat yang lebih dapat memberikan keyakinan. Namun kemudian
Plato mengoreksinya.
Bagi Plato kebenaran bersifat pasti dan tidak berubah-ubah. Kebenaran tidak
dipengaruhi oleh permainan kata, tidak pula dipengaruhi oleh perjalanan waktu dan
perubahan tempat. Kebenaran yang berubah-ubah adalah kebenaran palsu dan
menipu. Alasannya adalah kebenaran itu pasti dan tidak berubah, maka ia tidak
berasal dari sesuatu yang berubah setiap saat, akan tetapi berasal dari sesuatu yang
tetap.12
Kebenaran menurutnya adalah berasal dari dunia idea yang memang sudah
ada sebelumnya.13
Pernyataan Plato ini merupakan sebuah tanggapan terhadap
filosof sebelumnya yang menganggap bahwa dunia terus berubah. Hal tersebut
kemudian mengilhami Plato untuk tidak menetapkan materi sebagai landasan
kebenaran karena ia berubah-ubah. Di samping itu, Plato juga memandang bahwa
materi hanyalah sebuah bayangan dari apa yang ada dalam dunia idea.14
Maka dari
itu ia tidak bisa dijadikan sebagai landasan kebenaran.
Pemikiran Plato ini banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran umat
manusia sesudahnya termasuk umat Islam seperti Ibn „Arabī dan tokoh lainnya.
Dalam tradisi mistis Islam seperti pemikiran Ibn „Arabī pun meletakkan kebenaran
pada pengalaman batin yang metafisik dalam istilah Plato pengalaman langsung
tentang idea-idea. Seseorang akan mendapatkan kebenaran hakiki hanya ketika ia
meninggalkan keduniaan, tanpa itu kebenaran tidak akan pernah ia capai. Ibn „Arabī
menilai indera dan akal tidak mampu menyerap objek-objek eksternal secara
10
Hamid Algar, Murtaḍá Muṭahharī: Sang Mujahid, Sang Mujtahid, penerjemah.
Haidar Bagir, (Bandung: Mizan, 1988), h. 32. 11
A. Setyo WiboWo, “Pengantar Sejarah Filsafat Yunani: Sofisme”, makalah
filsafat, Komunitas Salihara, Maret 2016, h. 13. 12
Simon Petrus L. Tjahjadi, Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para
Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern, (Yogyakarta: Kanisius; 2008), h. 27. 13
Linda Smith & William Raeper, Ide-Ide Filsafat dan Agama, Dulu dan Sekarang,
(Yogyakarta: Kanisius; 2004), h. 17. 14
Jan Hendrik Rapar, Pengantara Filsafat, cet. ke-14, (Yogyakarta: Kanisius,
2010), 47.
4
langsung. Keduanya mempunyai keterbatasan-keterbatasan sehingga tidak akan
mampu menangkap objek metafisik yang merupakan wujud hakiki. Maka untuk
mendapatkan kebenaran, manusia hendaknya menyerap langsung objek-objek
tersebut melalui hati.15
Itulah yang disebut dengan pengalaman batin secara
langsung.
Seorang filosof asal Yunani yang juga terkenal hingga saat ini adalah
Aristoteles. Pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran dunia tidak diragukan
lagi. Dalam kajian tentang kebenaran, Aristoteles berpikir berbeda dengan
pendahulunya, Plato. Ia mengatakan kebenaran merupakan sesuatu pengetahuan atau
pernyataan yang terdapat kesesuaian atau identik dengan realitas satu sama
lainnya.16
Lebih jelasnya ia membedakan kebenaran dengan kekeliruan dengan
mengatakan “ketika seseorang mengatakan sesuatu yang tidak ada, atau yang tidak
ada sebagaimana adanya, maka ucapan tersebut merupakan kebohongan. Sebaliknya
mengatakan sesuatu yang ada sebagai ada, atau hal yang tidak ada sebagai hal yang
tidak ada merupakan kebenaran”.17
Dalam kalimat tersebut Aristoteles ingin
mengatakan bahwa kebenaran merupakan persesuaian antara pembawa kebenaran
dengan kenyataan. Suatu pernyataan dianggap benar jika sesuatu yang dinyatakan di
dalamnya berhubungan atau punya keterkaitan dengan kenyataan. Pemikiran
Aristoteles tersebut tampaknya berangkat dari pemikirannya yang mengatakan
bahwa pengetahuan atau pernyataan dalam akal bukan merupakan ide bawaan, akan
tetapi hasil dari abstraksi ide yang terdapat dalam bentuk benda-benda berdasarkan
hasil tangkapan indra. Itulah mengapa Adelbert Snijders mengemukakan bahwa
Aristoteles merupakan salah satu tokoh filosof yang mempertahankan keyakinan
bahwa segala pengetahuan diperoleh melalui indra.18
Naqīb al-„Aṭās menambahkannya, konsep korespondensi seperti yang
diungkapkan oleh Aristoteles dan pengikut setelahnya, merupakan konsep
kebenaran yang terlalu sederhana. Baginya kebenaran tidak hanya sekedar
kesesuaian antara pernyataan atau suatu pengetahuan dengan realitas, akan tetapi
lebih dari itu kebenaran juga seharusnya diikuti dengan manfaatnya. Fakta baginya
bisa saja diciptakan oleh manusia, maka bisa saja fakta berada pada tempat yang
salah. Maka dari itu, kebenaran yang sesungguhnya ialah kebenaran yang kemudian
membawa manfaat. Terdapat indikator-indikator tentang manfaat, yaitu
mendekatkan kepada Allah, dapat membantu manusia merealisasikan tujuan-
tujuannya, dapat memberikan pedoman kepada manusia dan dapat menyelesaikan
persoalan umat.19
Naqīb al-„Aṭās tampaknya menggabungkan konsep kebenaran
15
Ibn „Arabī, Futūḥāt al-Makkiyyah, ed. Maḥmūd Matrajī. Volume 8, (Bayrūt: Dār
al-Fikr, 2002), v. i, h. 288. 16
J. Sudarminta, Epistemologi Dasar, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 128. 17
A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan: Sebuat Tinjauan Filosofis
(Yogyakarta: Kanisius, 2010), cet. ke-10, h. 66. 18
Adelbert Snijders, Manusia dan Kebenaran: Sebuah Filsafat Pengetahuan,
(Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 51. 19
Achmad Charris Zubair, Filsafat Ilmu Menurut Konsep Islam, dalam Jurnal
Filsafat UGM, Maret 1997, h. 39. Diakses pada tanggal 04 September 2019 dari
https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/download/31650/19181
5
korespondensi dengan pragmatisme, meskipun konsep pragmatismenya berbeda
dengan pragmatisme Barat.
Sebagai bapak logika, Aristoteles juga menawarkan konsep lain selain yang
telah dijelaskan di atas yaitu konsep kebenaran yang kebenarannya tidak diukur oleh
realitas, namun diukur berdasarkan kaidah-kaidah logika. Menurutnya kebenaran
juga bisa didapatkan ketika suatu pernyataan atau suatu pengetahuan koheren20
atau
konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar atau sesuai dengan
kaidah-kaidah logika yang telah diuji kebenarannya.21
Teori kebenaran ini kemudian
banyak mempengaruhi pemikiran Islam. Tokoh-tokoh Islam yang mendapatkan
pengaruh pemikiran logika Aristoteles menurut Zainun Kamal di antaranya adalah
al-Fārābī, al-Ghazālī, Ibnu Rushd dan lainnya.
Al-Fārābī dapat dikatakan sebagai tokoh pemikir Islam pertama yang
meletakkan dasar-dasar teori kebenaran Aristoteles dalam dunia Islam. Ia juga
memberikan komentar-komentar yang begitu menawan atasnya. Secara garis besar,
pandangan al-Fārābī tentang teori kebenaran dapat dijabarkan bahwa suatu
kebenaran dapat kita temukan dengan menggunakan logika. Baginya logika telah
memberikan aturan-aturan yang dengannya kita dapat membedakan kebenaran dan
kesalahan. Dengan logika pola seseorang dapat memperoleh cara yang benar dalam
berpikir yang benar.22
Teori kebenaran ini oleh al-Fārābī digunakan untuk
membuktikan keberadaan Tuhan. Keberadaan Tuhan dikatakan benar ketika
argumen tentang keberadaannya sesuai dengan kaidah-kaidah logika. Dapat juga
dikatakan keberadaan Tuhan adalah benar ketika memiliki argumen-argumen
rasional.
Ibnu Sīnā sebagai filosof muslim yang mendapatkan gelar Syeikh Utama
filsafat juga mendapat pengaruh dari Aristoteles mengenai cara mencari kebenaran.
Untuk mendapatkan kebenaran dan mengetahui kekeliruan kita hendaknya
menggunakan akal atau logika.23
Maka bagi kedua tokoh tersebut, logika dapat
dikatakan sebagai alat untuk mengukur kebenaran. Dalam mengomentari teori
kebenarannya Aristoteles, ternyata Ibnu Sīnā memberikan pengayaan-pengayaan
yang luar biasa. Ibnu Sīnā mengembangkan teori kebenaran logis menjadi sebagai
suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri.
Filosof muslim yang kemudian mendewakan akalnya dalam mendapatkan
kebenaran adalah al-Rāzī. Al-Rāzī sangat mengagumi akal dan memujanya sehingga
cukup dengan akal, seseorang sudah mampu mendapatkan kebenaran. Kebenaran
baginya hanyalah semata-mata karena kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah logika.
Ia bahkan ia tidak mempercayai wahyu dan mengatakan bahwa al-Qur‟an bukan
mukjizat. Bahwa menurutnya tanpa hal tersebut akal sudah mampu menemukan
20
Daldiyono, Bagaimana Dokter Berpikir dan Bekerja, (Jakarta: Gramedia, 2006),
h. 169. 21
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 7. 22
Zainun Kamal, Ibn Taymiyah Versus Para Filosof Polemik Logika, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2006), h. 57. 23
Zainun Kamal, Ibn Taymiyah Versus Para Filosof ..., h. 60.
6
kebenaran.24
Pemikiran al-Rāzī tentang kebenaran ini tampaknya cukup ekstrem,
hingga tidak mengakui kebenaran selain kebenaran yang dihasilkan oleh akal.
Melihat filosof terdahulu yang begitu ekstrem memuja kemegahan teori
kebenaran Aristoteles berupa kebenaran logis, al-Ghazālī kemudian mengkritiknya.
Meskipun pada dasarnya al-Ghazālī juga mengakui keampuhan teori logika
Aristoteles dalam mencapai suatu kebenaran, namun di sisi lain al-Ghazālī
mengoreksinya. Baginya teori kebenaran Aristoteles itu memang mampu
memberikan kepada kita suatu jalan untuk mencapai kebenaran. Artinya logika
dapat digunakan untuk mengukur benar tidaknya suatu perkara, namun teori
kebenaran Aristoteles ini mempunyai kemampuan terbatas. Logika tidak dapat
mengukur kebenaran semua perkara. Terdapat banyak hal yang tidak dapat diukur
oleh teori kebenaran ini, terutama persoalan-persoalan yang bersifat metafisik.25
Di sinilah tampaknya al-Ghazālī menambahkan bahwa dalam rangka
mengukur kebenaran persoalan tidak hanya dapat menggunakan logika, tetapi
menggunakan intuisi. Ketika menghadapi persoalan metafisika maka hendaknya
menggunakan tolok ukur yang sesuai dengan karakter persoalan, maka intuisi adalah
cara memperoleh kebenaran yang tepat dalam mencapai kebenaran metafisika. Di
sinilah al-Ghazālī menunjukkan bahwa logika tak berdaya ketika menghadapi
metafisika.
Perdebatan tentang teori kebenaran tidak hanya terjadi pada pemikir muslim
tetapi juga di pemikiran Barat. Bahkan pemikiran-pemikiran Barat tentang teori
kebenaran bahkan sampai pada titik puncak sehingga lahir konsep yang tidak
mengakui kebenaran tentang keberadaan Tuhan. Namun dalam kaitannya dengan
teori kebenaran rasional, para filosof Barat yang mengkaji dan menggunakannya
sebagai landasan pengetahuannya ialah filosof Descartes, Spinoza, Hegel dan
lainnya.
Dalam kajian tentang teori kebenaran, Descartes melandaskannya pada akal.
Akal adalah satu-satunya alat untuk mendapatkan suatu kebenaran. Maka di sinilah
ia ingin mengatakan bahwa hanya dengan melalui berpikir manusia akan sampai
pada kebenaran hakiki. Kebenaran materi atau kebenaran yang didasarkan pada
materi menurutnya tidak dapat dikatakan sebagai kebenaran, karena indra (alat yang
digunakan untuk menangkapnya) cenderung menipu dan keliru. Maka seseorang
yang melandaskan kebenarannya pada indra maka mustahil sampai pada kebenaran.
Ia kemudian mencontohkan tentang warna langit. Ketika langit dilihat pada
siang hari, ia berwarna biru, padahal ia tidak berwarna biru. Maka dengan demikian
Descartes mengatakan bahwa semakin jelas suatu ide dalam akal budi, maka
semakin jelas sesuai ide tersebut dengan realitas.26
Pandangan Descartes ini
tampaknya menolak secara total peran indera dalam menangkap kebenaran. Maka
dunia materi oleh Descartes dinilai sebagai penampakan nisbi dan tidak dapat
dijadikan sebagai landasan kebenaran.
24
Harun Nasution, Falsafat dan Mistisisme dalam Islam, (Jakarta: Bulan bintang,
2008), h. 14. 25
Zainun Kamal, Ibn Taymiyah Versus Para Filosof ..., h. 63. 26
A. Soony Keraf dan Michael Dua, Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan Filosofis,
(Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 45.
7
Tentu saja teori kebenaran yang berlandaskan atas rasionalitas Descartes ini
tidak diterima setiap filosof di Barat. Terbukti lahir para kritikus-kritikus yang
melancarkan penolakan-penolakan dan menawarkan teori kebenaran lainnya.
Pemikiran mereka justru menjadikan apa yang ditolak oleh rasionalisme sebagai
landasan kebenaran.
Jika rasionalisme seperti dijelaskan tadi mencampakkan materi, akan tetapi
filosof seperti Karl Marx dan Engels justru menjadikan materi sebagai inti dari
realitas atau fakta. Apa yang selama ini oleh Descartes, Spinoza dan teman-
temannya dianggap sebagai realitas sejati, oleh Marx dan Engels tak dianggap
sebagai realitas. Maka bagi Marx dan Engels yang ada hanyalah sesuatu yang dapat
ditangkap oleh indera atau yang biasa kita sebut materi.27
Dengan demikian realitas
sejati adalah sesuatu yang bersifat materi.28
sedangkan materi adalah sesuatu yang
ditangkap atau diamati oleh pancaindra.29
Dalam melihat kebenaran pun berlandaskan materi. Segala yang tidak
mempunya bentuk materi olehnya dianggap sebagai kebohongan dan kekeliruan.
Maka kebenaran bagi mereka adalah kesesuaian dengan fakta. Sedangkan fakta
adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh pancaindra. Suatu pernyataan atau
teori dianggap benar adanya ketika ia mempunyai bukti materiil atau fakta. Segala
sesuatu yang tidak terdapat fakta di dalamnya, maka sesuatu itu adalah
kebohongan.30
Termasuk teori tentang ketuhanan. Keberadaan Tuhan akan dikatakan
benar ketika Tuhan dapat dibuktikan secara materi. Jika ia tidak dapat dibuktikan
secara materi maka keberadaan Tuhan adalah kebohongan. Maka begitulah mereka
mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Kesimpulannya adalah fakta/materi adalah
faktor yang menentukan kebenaran.
Jika memang hanyalah benda yang ada, dan setiap kebenaran harus
dibuktikan menggunakan eksperimen maka manusia terutama masyarakat beragama
akan banyak kehilangan kebenaran. Karena teori-teori keagamaan selama ini
dibangun atas dasar rasionalitas dan kesaksian batin. Banyak ajaran-ajaran dari
agama yang tidak ada relevansinya dengan materi, ajaran agama bersifat metafisik.
Metafisik adalah sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara eksperimen atau dengan
pengamatan pancaindra.
Teori ini tentunya tidak digunakan oleh filosof muslim dalam menentukan
kebenaran tentang keberadaan Tuhan. Teori kebenaran yang mengandalkan indera
sebagai ujung tombak kebenaran banyak mendapatkan tantangan dari kalangan umat
Islam. Secara umum pemikir Islam mengungkapkan kelemahan-kelemahan indra
dalam menangkap realitas.
Umat Islam yang mengungkap kelemahan-kelemahan indra ialah Ibnu Sīnā.
Baginya sesuatu yang bersifat materi mempunyai kelemahan-kelemahan. Terkadang
27
Franz Magnis Suseno, Dalam Bayang-Bayang Lenin: Enam Pemikiran Marxisme
Dari Lenin Sampai Tan Malaka, (Jakarta: Gramedia, 2016), cet. iii, h. 22-24. 28
Bryan Magee, The Story of Philosophy, Penerjemah Marcus Widodo dan
Hardono Hadi (Yogyakarta: Kanisius, 2012), cet. ke-5, h. 36. 29
Oesman Arif, Dasar-Dasar Ilmu Filsafat Timur dan Barat, (Solo: Matakin,
2009), h. 129. 30
Jujun S. Suriasumantri, Ilmu dalam Perspektif, (Jakarta: Gramedia, 1978), h. 70.
8
materi tampak kepada manusia tidak sebagaimana adanya. Di antara kekeliruan yang
dapat muncul pada materi di antaranya ialah 1. Kekeliruan karena jarak objek yang
terlalu jauh dari jarak moderat. 2. Posisi objek yang terlalu jauh dari jarak moderat.
3. Karena pencahayaan yang terlalu terang dari pencahayaan moderat. 4. Karena
ukuran objek yang terlalu kecil atau terlalu besar dari ukuran moderat. 5. Karena
keburaman yang terlalu pekat. 6. Karena transparansi yang terlalu kuat dari moderat.
7. karena lamanya memandang yang berada di luar batas moderat dan 8. Karena
kondisi mata yang tak memungkinkan akibat kerusakan yang melampaui batas
moderat.31
Ketika sesuatu yang tampak kepada manusia adalah sesuatu yang tidak
sebagaimana adanya, maka hal yang tampak tersebut bukanlah kenyataan hakiki.
Maka Ibnu Sīnā mengelompokkan kenyataan menjadi 3 golongan di antaranya ialah
kenyataan yang secara niscaya tidak berkaitan dengan materi dan gerak, kenyataan
yang meskipun pada dasarnya imateriil tetapi terkadang mengadakan kontak dengan
materi dan gerak dan kenyataan yang secara niscaya berhubungan dengan materi dan
gerak.32
Tidak hanya Ibnu Sīnā yang mengungkap kelemahan indra, tetapi juga al-
Ghazālī. Dalam pandangannya, materi tidak bisa dijadikan landasan realitas, karena
pancaindra yang dijadikan alat penangkap pengetahuan tentang materi kerap kali
menipu seseorang. Ia menilai pancaindra memiliki keterbatasan dan tidak dapat
mencapai kebenaran.33
Tongkat yang lurus akan tampil bengkok ketika dimasukkan
ke dalam air, padahal aslinya tidak bengkok. Tidak hanya itu, bintang yang oleh
manusia dilihat sebagai benda kecil ternyata ia sangat besar. Apa yang dikatakan
oleh al-Ghazālī menunjukkan bahwa materi yang merupakan sesuatu yang ditangkap
pancaindra tidak dapat dijadikan landasan kebenaran, karena ia sering keliru.
Immanuel Kant justru sangat ekstrem dengan mengatakan kebenaran hakiki
tidak akan pernah manusia dapatkan. Baginya melandaskan kebenaran pada
kenyataan adalah hal yang mustahil, karena kenyataan hakiki tidak dapat diketahui
oleh manusia. Kenyataan yang biasa manusia bahas hanyalah “kenyataan yang
diketahui”. “Kenyataan yang diketahui” bukan lah kenyataan sebenarnya, karena
manusialah yang sebenarnya memberikan isi dan bentuk kepada kenyataan tersebut
dan menjauhkan kita dari kenyataan yang sebenarnya.34
Dari berbagai keterangan di atas tampaknya terdapat sebagian pemikiran
para tokoh yang cukup ekstrem dalam mengonsep teori kebenarannya. Seperti teori
kebenaran Plato yang menolak kemampuan indra sebagai alat penangkap kebenaran
materi. Di sebabkan karena materi yang terus berubah. Di sisi lain Karl Marx dan
Engles menafikan kebenaran selain materi.
Pemikiran materialisme ini hadir di tengah masyarakat muslim Iran. Ajaran-
ajarannya terus dihembuskan kepada masyarakat. Banyak pemuda-pemuda mulai
31
Mulyadi Kartanegara, Pengantar Epistemologi Islam, (Bandung: Mizan, 2003), h.
77. 32
Mulyadi Kartanegara, Pengantar Epistemologi Islam ..., h. 43. 33
M. Solihin. Perkembangan Pemikiran Filsafat Dari Klasik Hingga Modern
(Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 43. 34
Adelbert Snijders, Manusia Kebenaran ..., h. 20.
9
terpengaruh oleh ajaran-ajaran materialisme dan ajaran-ajaran Barat lainnya. Ajaran-
ajaran Barat yang oleh Murtaḍá dianggap sebagai ajaran menyesatkan justru menjadi
idola umat muslim. Hal tersebut membuat Murtaḍá mengkaji dan mengkritik ajaran-
ajaran Barat tanpa menghilangkan objektivitasnya. Terbukti meskipun ajaran-ajaran
Barat ia katakan menyesatkan, namun ajaran-ajaran yang dianggapnya benar tetap ia
ambil sisi kebenaran dari pemikiran-pemikiran tersebut.
Maka Murtaḍá Muṭahharī muncul sebagai kritikus dan penyatu dari berbagai
pandangan Barat yang menyesatkan. Ia tampil sebagai sosok pengkritik teori idea
Plato dan membela materialisme Marx. Serta mengkritik materialisme Marx dan
membela idealisme Plato. Pemikiran-pemikiran tentang teori kebenarannya banyak
tertulis dalam bukunya yang berjudul Mas'ala-ye Syenokh (Mengenal Epistemologi).
Murtaḍá mengkritik teori kebenaran Plato yang mendasarkan kebenaran hanya
semata-mata pada dunia idea. Teori Plato yang mengatakan kebenaran hanyalah ada
di dunia idea adalah tidak benar. Plato sama saja dengan mengingkari kebenaran
yang sudah di depan mata dan dilakukan setiap hari. Keputusan Plato dalam
menghapus kebenaran materi adalah keputusan yang tidak bijak, mengingat terdapat
kebenaran selain yang Plato sampaikan.
Dalam membuktikan kebenaran fisik Murtaḍá mencontohkan tentang ilmu
kedokteran dikatakan bahwa “sesuatu itu” adalah penyebab munculnya penyakit
kanker. Ini dapat dikatakan benar ketika “sesuatu itu” memang terbukti secara lahir
dapat menyebabkan munculnya penyakit kanker. Sebaliknya jika tidak maka ia tidak
benar.35
Dalam penelitian kedokteran pembuktian-pembuktian seperti itu telah
terbukti mampu menciptakan ilmu yang tidak terbayangkan sebelumnya.
Meskipun Murtaḍá menolak ekstremisme Plato dalam menyajikan teori
kebenaran dengan menolak teori kebenaran materialis secara total, namun dalam
buku epistemologinya Murtaḍá tidak melontarkan penolakan terhadap teori
kebenaran Plato. Itu artinya Murtaḍá mengakui bahwa terdapat kebenaran idea,
tetapi juga mengakui bahwa terdapat kebenaran materi.
Dari sinilah tampak bahwa Marx dan Engels mempunyai posisi ruang dalam
pemikiran Murtaḍá. Di tengah masyarakat muslim yang mengkritik teori kebenaran
materialisme, Murtaḍá tampil sebagai sosok yang membelanya dan menjelaskan
secara objektif tentang teori kebenaran kedua. Murtaḍá mengakui dalam kekeliruan
teori Marx masih terdapat serpihan-serpihan kebenaran yang mungkin kita abaikan.
Meskipun teori materialisme Marx dan Engels telah menghantam teori
metafisika Islam, namun tampaknya Murtaḍá mencoba untuk objektif menilai teori
mereka dengan tidak menolak keseluruhan dari teori materialisme. Tampak dalam
bukunya ia dalam teori materialisme terdapat sisi kebenaran yang telah terbukti
secara nyata. Bahkan kebenaran materi telah diakui oleh al-Qur‟an.36
Dari sini lah
tampaknya analisa Murtaḍá tidak dipengaruhi oleh keyakinannya.
Dalam merumuskan teori-teori ini, Murtaḍá juga tidak hanya mengandalkan
analisa akalnya. Tetapi dalam tiap bahasannya banyak menyertakan ayat-ayat
sebagai landasan berpijaknya. Tidak heran jika banyak orang menilai teori
35
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Epistemologi Islam, Penerjemah Muḥammad
Jawad Bafaqih, (Jakarta: Shadra Press, 2010), h. 216-217. 36
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Epistemologi Islam ..., h. 78.
10
kebenaran Murtaḍá ini adalah teori kebenaran yang bersifat Qur‟ani. Sebuah teori
kebenaran yang lahir dari rahim ayat-ayat Qur‟an.
Di sisi lain Murtaḍá mengkritik kebenaran kesepakatan (ulama) seperti yang
dilakukan Ahlussunnah. Kesepakan para ulama bisa saja menghasilkan sesuatu yang
tidak benar, padahal kebenaran bukan terjadi karena disepakati, tetapi disepakati
karena ia benar. Dalam mengkritik teori ijmaʻ Ahlussunnah, ia menyoroti kasus
penentuan hukum Ahlussunnah yang berubah-ubah dalam gurun waktu tertentu.
Menurutnya kebenaran tentang hukum Allah tidak pernah berubah dari waktu ke
waktu, jika ada perubahan maka sudah pasti salah satunya ada yang salah.37
Pada akhirnya menurut Murtaḍá kebenaran tidak selamanya terjadi
kesesuaian antara pernyataan atau teori dengan realitas eksternal.38
Baginya terdapat
juga kebenaran yang tak dapat dikaitkan dengan realitas eksternal seperti lingkaran,
segi 10, kebenaran tentang keberadaan Tuhan. Semua yang disebutkan Murtaḍá
terakhir ini adalah sesuatu yang memang tidak mempunyai realitas materi sehingga
ia tidak dapat dibuktikan dengan eksperimen atau pembuktian lain yang bersifat
materi.
Bahkan terdapat suatu teori yang mengatakan bahwa kebenaran merupakan
suara mayoritas yang berada di wilayah tersebut. Kebenaran baginya merupakan
adalah mayoritas, suatu kebenaran yang berada di luar diri seseorang.39
Itu artinya,
jika mayoritas mengatakan bahwa suatu pembawa kebenaran adalah benar, maka
benar pula pembawa kebenaran tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Jean Jacques
Rousseau bahwa suara mayoritas merupakan tolok ukur dari kebenaran.40
Kepentingan umum yang tertuang dalam suara mayoritas merupakan landasan
dalam menentukan benar tidaknya sesuatu. Jika mayoritas menganggap suatu konten
benar, maka ia adalah benar.
Perdebatan-perdebatan tersebut membuat penulis ingin mengkaji lebih
mendalam teori tentang kebenaran yang dikhususkan pada pemikiran Murtaḍá
Muṭahharī tentang kebenaran. Muṭahharī dalam teori kebenarannya menawarkan
pandangan yang komprehensif. Baginya kebenaran tidak hanya bisa dikategorikan
sebagai kebenaran materiil, tetapi ada empat kebenaran. Di antaranya kebenaran
yang dimaksud ialah kebenaran yang berkaitan dengan indra yaitu kebenaran
materiil, akal yaitu kebenaran logis, hati yaitu kebenaran yang jiwa dan sejarah yaitu
kebenaran suatu kisah dengan bukti-bukti sejarah.41
Keempat kebenaran yang
dipaparkannya ialah kebenaran yang sudah dilegitimasi oleh al-Qur‟an. Yang
menarik dari teori kebenaran Muṭahharī ialah teori kebenaran yang ia sajikan sangat
komprehensif, filosofis dan melandaskan teorinya pada al-Qur‟an.
37
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Epistemologi Islam ..., h. 246-247. 38
Murtaḍá memahami realitas eksternal adalah yang bersifat materi sebagaimana
Aristoteles jelaskan. 39
Ridwan Zachrie dan Wijayanto, Korupsi mengorupsi Indonesia: sebab, akibat,
dan prospek pemberantasan, (Bandung: Gramedia, 2013), h. 902. 40
Simon Petrus L. Tjahjadi, Petualangan Intelektual ..., h. 265-269. 41
Murtaḍá Muṭahharī, Mengenal Epistemologi: Sebuah Pembuktian Terhadap
Rapuhnya Pemikiran Asing dan Kokohnya Pemikiran Islam, Penerjemah M.J. Bafaqih,
(Jakarta: Lentera, 2001), h. 87.
11
Sepak terjang pemikiran Murtaḍá dalam teori kebenaran ini, tampaknya
cukup menarik jika dibahas lebih jauh dan detail. Maka dari itu, penulis
menginginkan untuk membedahnya sampai tuntas dalam penelitian kali ini. Maka
penulis memutuskan untuk meneliti teori kebenaran Murtaḍá dengan judul
penelitian “Teori Kebenaran Murtaḍá Muṭahharī”.
B. Identifikasi Masalah
1. Terdapat banyak pendapat yang membahas teori kebenaran mulai dari Barat
hingga Islam.
2. Teori kebenaran yang ditawarkan oleh materialisme sangat ekstrem memandang
landasan kebenaran satu-satunya hanyalah materi.
3. Teori kebenaran idealisme juga ekstrem. Ia memandang landasan dari kebenaran
adalah hanya idea.
4. Dalam Islam seperti sufi, menganggap kebenaran yang hakiki hanyalah
pengalaman batin bersama Tuhan.
5. Filosof muslim sebagian menganggap bahwa akal adalah landasan paling baik
untuk mendapatkan kebenaran.
6. Murtaḍá Muṭahharī mengkritik konsep-konsep filosof Barat dan muslim. di
samping mengkritik ia juga menerima sebagian pendapat-pendapat mereka.
7. Terjadi penolakan radikal kepada pemikiran Barat oleh sebagian kalangan umat
Islam.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis kemudian merumuskannya
ke dalam perumusan masalah di antaranya ialah bagaimana konsep kebenaran
menurut Murtaḍá Muṭahharī dan kritiknya terhadap teori kebenaran Barat?
D. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah penelitian pada pemikiran
Murtaḍá Muṭahharī tentang kebenaran. Di antara kebenarannya yang akan dibahas
ialah mengenai landasan-landasan kebenaran Murtaḍá Muṭahharī seperti alat-alat
dalam mendapatkan kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran, serta bagaimana cara
mencapai kebenaran yang ditulis oleh Murtaḍá dalam buku primernya.
Di samping itu juga penulis akan menambahkan pembahasan tentang
kritiknya terhadap pemikiran Barat tentang kebenaran. Adapun pemikiran Barat
yang akan dikritik oleh Murtaḍá Muṭahharī ialah pemikiran tentang kebenaran
menurut materialisme yang diwakili oleh Karl Marx, rasionalisme seperti Descartes
dan empirisme yaitu Auguste Comte.
E. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah
1. Untuk memahami teori kebenaran menurut Murtaḍá Muṭahharī.
a. Untuk memahami indikator-indikator kebenaran menurut Murtaḍá
Muṭahharī
b. Untuk mengetahui langkah-langkah untuk mencapai kebenaran
12
F. Manfaat Penelitian
1. Signifikansi Penelitian
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi filsafat Islam berupa
pengayaan penelitian di bidang filsafat Islam terutama kajian teori kebenaran.
2. Manfaat Penelitian
Secara praktis, penelitian ini akan mempermudah dan memperjelas
pemahaman masyarakat terhadap pemikiran Murtaḍá Muṭahharī tentang konsep
kebenaran. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi masyarakat
dalam melakukan verifikasi suatu ilmu pengetahuan sehingga benar tidaknya suatu
pengetahuan dapat diidentifikasi dengan baik.
Sedangkan manfaat akademik. Penelitian ini tentu akan memperkaya
khazanah kajian-kajian akademik. Dengan adanya kajian ini, setidaknya
masyarakat akan mempunyai tawaran penjelasan baru tentang konsep kebenaran
Murtaḍá Muṭahharī dan mengetahui lebih detail kritiknya terhadap pemikiran
Barat.
G. Kajian Pustaka
Kajian tentang teori kebenaran bukanlah sesuatu tema yang baru dalam
kajian tentang filsafat, begitu juga kajian tentang pemikiran Murtaḍá Muṭahharī.
Maka dari itu, penelitian-penelitian yang satu tema dan satu tokoh dengan penelitian
ini akan saya paparkan di bawah. Selain sebagai bahan bacaan, penelitian terdahulu
ini akan disajikan oleh penulis sebagai gambaran tentang posisi penelitian ini di
antara berbagai kajian tentang teori kebenaran dan Murtaḍá Muṭahharī.
Di antara berbagai penelitian yang setema di antaranya adalah penelitian
yang mendekati penelitian penulis ialah penelitian yang berjudul “Prinsip-prinsip
Epistemologi dalam Pemikiran Murtaḍá Muṭahharī” ditulis oleh Syahrul Nizar
Saragih dalam penelitian tesisnya pada tahun 2005. Penelitian tersebut sebenarnya
lebih fokus kepada epistemologi Murtaḍá Muṭahharī dalam kaitannya dengan
rangkaian ideologi dan pandangan alam. Menurutnya epistemologi merupakan
bagian penting dari rangkaian ideologi dan pandangan alam. Ideologi baginya
adalah berisi tentang muatan panduan, peraturan dan cara orang memandang hidup.
Sedangkan isi ideologi berasal dari pandangan alam. Pandangan alam adalah bentuk
dari suatu kesimpulan, penafsiran hasil kajian, yang ada pada orang berkenaan
dengan alam semesta, manusia masyarakat dan sejarah.
Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian
yang dilakukan oleh Nizar berfokus pada epistemologi secara global. Epistemologi
yang ia jelaskan menyangkut peran dan posisi epistemologi dalam ideologi dan
pandangan alam. Penelitian penulis fokus pada teori kebenaran yang meliputi
definisi, cara mendapatkan kebenaran unsur-unsur dasar kebenaran yang kemudian
dikaitkan dengan kritiknya terhadap pemikiran Barat tentang kebenaran. Penelitian
penulis ini justru akan melengkapi penelitian yang telah dilakukan oleh Nizar.
Penelitian tersebut sangat berarti bagi penelitian ini sebagai pengayaan bacaan dan
informasi yang nanti akan semakin memperkuat analisa dalam penelitian ini.
Penelitian satu tokoh dengan penulis ialah penelitian Ahmad Faqihuddin,
mahasiswa S2 UIN Syarif Hidayatullah dengan judul penelitian “Kritik Murtaḍá
13
Muṭahharī terhadap Marxisme”. Penelitian tesis ini dilakukan pada tahun 2008
dengan yang dibimbing oleh Prof. Dr. Zainun Kamal dan Prof. Dr. Amsal Bakhtiar.
Dalam penelitiannya penelitian ini fokus pada kritik terhadap teori materialisme
sejarah dan ekonomi Karl Marx. Menurut pemahaman Ahmad dalam mengkaji
kritik Murtaḍá, ia mengatakan bahwa unsur-unsur hewani dalam diri manusia
menurut Murtaḍá tetap tidak berubah sejak permulaan sejarah hingga sekarang.
Namun pembawaan manusiawinya secara bertahap berkembang. Ia akan mampu
membebaskan dirinya dari ikatan-ikatan bendawi dan ekonomi serta cenderung ke
arah keimanan dan kesempurnaan rohani. Dasar berpijak perkembangan sejarah
bukanlah perjuangan-perjuangan untuk kepentingan kelas dan keuntungan duniawi,
melainkan perjuangan ideologi dan rohani yang berdasarkan keimanan kepada
Allah.
Dalam memandang ekonomi dan agama, Karl Marx mengatakan bahwa
agama adalah merupakan hasil penderitaan masyarakat terhadap ekonomi dan
penindasan penguasa. Dalam ajaran agama terdapat doktrin kesabaran dan
mendorong pasivitas yang nanti justru akan membuat masyarakat terus menerus ada
dalam kemiskinan. Sedangkan menurut Murtaḍá Muṭahharī memandang justru
agama menjadi lokomotif kemajuan di bidang ekonomi dan mengajarkan kepada
umatnya agar cepat tidak menyerah.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian Ahmad
fokus pada kajian dan kritik Murtaḍá Muṭahharī terhadap materialisme khususnya
tentang sejarah dan ekonomi. Sedangkan penulis fokus pada kajian tentang teori
kebenaran Murtaḍá Muṭahharī. Namun penelitian tersebut oleh penulis akan
dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan tentang pemikiran
Murtaḍá, sehingga pemahaman penulis terhadap teori kebenarannya lebih detail dan
mendalam.
Akademisi yang meneliti pemikiran Murtaḍá Muṭahharī adalah Nurmala
Buamona mahasiswa S2 jurusan pemikiran pendidikan Islam pada UIN Jogja
dengan judul Pemikiran Murtaḍá Muṭahharī tentang Etika dan Implementasinya
dalam Pembentukan Karakter. Dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa yang
mengatur kekuatan manusia adalah akal. Akal merupakan sumber dari etika yang
melahirkan kehendak dan menjadi hakim mutlak perilaku manusia. Keadilan
menjadi landasannya dan agama sebagai jalan yang mengantarkan manusia menuju
sempurna. Penelitian ini cukup jelas, terdapat perbedaan tema yang dibahas,
meskipun tokoh yang dibahas sama.
Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Charris Zubair dalam jurnal Jurnal
Filsafat UGM, Maret 1997 dengan judul “Filsafat Ilmu menurut Konsep Islam”
merupakan penelitian yang satu tema dengan penulis. Dalam uraiannya, Charris
mengatakan bahwa suatu hal dapat dikatakan mengandung kebenaran apabila ia
mempunyai manfaat dalam arti luas. Suatu kebenaran akan menjadi sebagai
kebenaran sesungguhnya jika sesuai dengan tuntutan-tuntutan kearifan dan keadilan.
Itu berarti bahwa kebenaran bukan hanya suatu korespondensi antara pernyataan
dengan fakta, akan tetapi kebenaran harus didasarkan pada penafsiran yang benar
dan itu pasti mengandung suatu manfaat yang sesungguhnya. Di antara manfaat
yang dimaksud ialah pertama, mendekatkan pada kebenaran Allah. Kedua, dapat
14
membantu umat merealisasikan tujuan-tujuannya. Ketiga, ialah dapat memberikan
pedoman bagi manusia dan terakhir ialah menyelesaikan persoalan umat. Kebenaran
seperti yang ditawarkan oleh positivisme seperti rekayasa genetika. Teori rekayasa
genetika tidak dapat dikatakan sebagai kebenaran meskipun ia berdasarkan fakta
yang benar, karena ia dibangun di atas premis-premis yang didasarkan pada
penafsiran yang salah tentang hakikat manusia.
Kajian tentang kebenaran yang lain yang ditemukan oleh penulis ialah hasil
penelitian mahasiswa Pascasarjana IAIN Ar-Raniry yang bernama Saifuddin dengan
judul “Kajian Agama Dan Filsafat Tentang Kajian Kebenaran”. Penelitian tersebut
menyoroti tentang suara publik yang mempertentangkan antara jalan agama dan
filsafat dalam mencapai kebenaran. Dalam penelitian yang terbitkan pada jurnal
Islam Futura ini disebutkan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan pada pola dasar
antara agama dan filsafat. Di antaranya ialah agama didasarkan pada wahyu yang
bersifat absolut sedangkan filsafat mendasarkan pada pemikiran atau akal universal.
Perbedaan tersebut bukan merupakan pertentangan. Ketika kita mengkajinya lebih
mendalam maka akan justru saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya.
Perspektif berbeda dari keduanya akan melahirkan keragaman dalam pemahaman
dan itu akan memperkuat sebuah argumen tentang sesuatu. Bahwa perbedaan itu
akan membuktikan kebenaran sesuatu yang sama.
Contoh dari apa yang dijelaskan di atas adalah mengenai kajian tentang
pembuktian kebenaran keberadaan Tuhan. Agama menggunakan argumen tekstual
dalam membuktikannya, sedangkan para filosof menggunakan akal. Dan ternyata
dalam kajian ketuhanan dalam Islam, terdapat kesamaan hasil. Antara filsafat dan
agama sama-sama menemukan kebenaran bahwa tuhan adalah ada. Hanya saja
argumennya yang berbeda. Penelitian ini diterbitkan pada tahun 2008 pada Jurnal
Futura vol. Ii No. 2. Meskipun temanya sama-sama membahas tentang kebenaran,
akan tetapi ia fokus pada komparasi kebenaran antara agama dan filsafat. Sehingga
pembahasannya sangat berbeda dengan penulis akan tetapi kajiannya sangat dekat,
sehingga kajian ini bisa dijadikan sebagai pengayaan informasi tentang teori
kebenaran.
Kajian berikutnya ialah hasil penelitian Imron Mustofa. Ia merupakan
akademisi yang pernah meneliti tentang kebenaran yang kemudian ia publikasikan
di Jurnal Kalimah dengan judul “Konsep Kebenaran Ibnu Sīnā”. Tulisan tersebut
tertuang dalam jurnal tepatnya pada Vol. 15, No. 1, Maret 2017. Dalam kajiannya ia
menyimpulkan bahwa kebenaran merupakan keterhubungan atau kesesuaian antaran
ilmu, kenyataan dan perasaan. Kebenaran menurutnya terbagi menjadi tiga yaitu
kebenaran wahyu, kebenaran yang dapat dibuktikan eksistensinya dan kebenaran
filsafat. Kebenaran berawal dari persepsi inderawi, kemudian akal. Ini adalah tahap
pembukaan. Meskipun demikian, pengetahuan kebenaran diperoleh melalui jalur di
luar akal manusia yaitu intuisi atau emanasi dari akal aktif yaitu akal yang terpisah
dari materi.
Tema penelitian ini sama yaitu membahas tentang teori kebenaran hanya
saja tokoh yang diangkat berbeda. Dalam setiap tokoh tentunya mempunyai khas-
15
khas tersendiri termasuk dalam pemikiran Murtaḍá Muṭahharī yang mempunyai
perbedaan pendapat dengan Pemikir Islam yang lain termasuk dengan Ibnu Sīnā.
Meskipun Muṭahharī juga mengutip pemikiran Ibnu Sīnā ketika membahas tentang
teori kebenaran, namun kenyataannya teorinya tidak sama persis dengan teori Ibnu
Sīnā. Kalau Muṭahharī beranggapan bahwa indra mempunyai peran penting
sebagaimana pentingnya akal dan hati dalam mendapatkan kebenaran yang bersifat
materi, sedangkan Ibnu Sīnā mengatakan bahwa pentingnya indra terdapat di
permulaan, akan tetapi kebenaran didapatkan dari intuisi atau emanasi dari akal aktif
yang terpisah dari materi.
Setelah penulis kumpulkan dan amati hasil penelitian yang dianggap
mempunyai kesamaan tema, penulis tidak menemukan penelitian yang benar-benar
sama persis dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Maka penelitian yang
akan dilakukan di sini bukanlah pengulangan penulisan, akan tetapi justru akan
memperkaya kekayaan pembahasan yang telah dilakukan oleh para peneliti
terdahulu. Tentunya penelitian-penelitian terdahulu tersebut akan penulis jadikan
sebagai referensi yang akan menambah wawasan penulis sehingga penelitian ini
menjadi lebih baik.
H. Metodologi Penelitian
a) Bentuk Penelitian
Jika dilihat dari sumber datanya dapat dikatakan sebagai penelitian
kepustakaan. Dikatakan sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian ini
mengkaji pemikiran yang ada dalam tulisan Murtaḍá Muṭahharī. Sebagai mana
dikatakan oleh Kun Zachrun Istanti bahwa penelitian kepustakaan dilakukan
untuk mencari dan meneliti naskah-naskah, artikel-artikel ataupun sumber-
sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, baik
yang tersimpan di perpustakaan maupun di museum.42
Dilihat dari perspektif analisisnya maka penelitian ini termasuk kepada
penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Subroto43
adalah metode
pengkajian atau metode penelitian suatu masalah yang tidak didesain atau
dirancang menggunakan prosedur-prosedur statistik. Sedangkan menurut Eko
Sugiarto penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang temuan-temuannya
tidak diperoleh melalui prosedural statistik atau bentuk hitungan lainnya dan
bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui
pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai
instrumen kunci.44
42
Kun Zachrun Istanti, Metode Penelitian Filologi dan Penerapannya,
(Yogyakarta: Elmatera, 2010), h. 51. 43
Edi Subroto, Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural (Solo: LPP dan
UPT Penerbit dan Pencetakan UNS, 2007), h. 5. 44
Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Kripsi dan Tesis
(Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 8. Diakses dari
https://books.google.co.id/books?id=jWjvDQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=penelitian
+kualitatif+adalah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjbhf6AwJHdAhVJOY8KHQvBA5gQ6AE
INDAB#v=onepage&q=penelitian%20kualitatif%20adalah&f=false.
16
Sedangkan kalau dilihat dari tujuan penyelenggaraan penelitian ini
dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analitik. Penelitian deskriptif
adalah penelitian yang dilakukan untuk memberi gambaran lebih detail tentang
suatu gejala.
b) Sumber Data
Sumber data dibedakan menjadi 2, yaitu sumber data primer dan
sekunder. Sumber data primer adalah sumber data utama yang berkaitan
langsung dengan pemikiran tokoh seperti karya tokoh yang akan dikaji. Dalam
penelitian ini sumber primer dari penelitian ini adalah buku karya Murtaḍá
Muṭahharī yang membahas tentang teori kebenaran. Karya-karyanya ialah
Neraca Kebenaran dan Kebatilan, Pengantar Epistemologi, Manusia dan
Takdirnya, Jejak-jejak Rohani dan lainnya.
Sumber data sekunder adalah data pendukung yang tidak berkaitan
langsung dengan penulis. Data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku
yang membahas teori kebenaran yang berasal dari buku-buku filosof muslim
dan filosof Barat. Di samping itu juga, hasil penelitian-penelitian peneliti
tentang teori kebenaran.
c) Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui pembacaan
yang seksama terhadap teks-teks pemikiran yang dianggap berkaitan dengan
tema penelitian. Setelah membaca dengan seksama, hasil pemahaman
kemudian dikumpulkan. Setelah dikumpulkan kemudian, diklasifikasikan
sesuai dengan sub-sub pembahasan.
d) Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat. Tujuannya ialah untuk
mengkaji secara mendalam pemikiran teori kebenaran Murtaḍá Muṭahharī yang
memang ia menulisnya dari sudut pandang filosofis. Pendekatan filsafat dalam
penelitian ini sangat penting untuk menganalisa pemikiran Murtaḍá Muṭahharī
serta kritiknya terhadap pemikiran Barat.
e) Analisis data
Penulis mengklasifikasikan tema-tema berdasarkan daftar isi. Data-data
yang sudah diklasifikasikan kemudian dibahas dan dianalisa kekuatan
argumennya dengan cara mengujinya menggunakan teori-teori lain tentang
kebenaran yang sudah diakui.
Teori kebenarannya sudah diungkap kemudian menelisik argumen-
argumen Muṭahharī dalam mengkritik pemikiran Barat. Sejauh mana kekuatan
argumentasinya dalam mengkritik mereka atau malah lebih lemah dari argumen
mereka. Dalam menganalisanya menggunakan pendekatan filosofis untuk
mendapatkan hasil yang mendalam.
I. Sistematika Pembahasan
Bab i pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pendahuluan,
metodologi penelitian, sistematika penulisan.
17
Bab ii membahas tentang teori kebenaran. Pada bab ini akan membahas dua
hal, yaitu pandangan filosof Islam tentang kebenaran dan pandangan filosof Barat
tentang kebenaran. Pemikiran tokoh Islam tentang teori kebenaran yang akan
dibahas di sini meliputi pandangan al-Ghazālī, Ibnu Sīnā, Muḥammad Naqīb al-
„Aṭās, Muḥammad Taqī Miṣbāḥ Yazdī dan Mula Shadra. Sedangkan pandangan
tokoh Barat ialah meliputi René Descartes sebagai wakil dari rasionalisme, Bertrand
Russel dan Francis Bacon sebagai wakil dari empirisme, Charles S. Peirce
pragmatisme.
Biografi Murtaḍá Muṭahharī dibahas pada bab iii. Di antara bagian-
bagiannya ialah riwayat hidup dan pendidikan Muṭahharī. Pada sub bab ini dibahas
secara tuntas riwayatnya, mulai dari sejak lahir hingga ia wafat. Di samping itu juga
akan dibahas tentang guru-guru yang mempengaruhinya. Juga pemikiran seperti apa
yang mempengaruhinya. Serta juga akan dibahas kondisi sosial pada setiap
perjalanan hidupnya.
Sub bab bagian dua membahas tentang daftar karyanya serta resensi dari
karya-karyanya. Karya-karya Murtaḍá Muṭahharī cukup banyak, tetapi akan penulis
sajikan satu persatu sesuai dengan kemampuan penulis. Kemudian pada sub bab
bagian tiga, penulis akan membahas peran Murtaḍá Muṭahharī dalam pemikiran
Islam. Sumbangan apa saja yang ia berikan kepada pemikiran perkembangan Islam.
Bab berikutnya ialah bab iv. Bab ini berisi tentang Epistemologi Kebenaran,
Prinsip-Prinsip Kebenaran, Metode Mencari Kebenaran dan Kritik Murtaḍá
Muṭahharī kepada Barat. Epistemologi kebenaran yang di maksud di sini adalah
landasan dasar dari teori kebenarannya. Bagaimana prosesnya sehingga dia
berkesimpulan sebagaimana ia pahami tentang teori kebenaran. Prinsip-prinsip
kebenaran di sini membahas tentang apa saja hal-hal yang membuat suatu teori atau
pengetahuan itu benar. Pembahasan selanjutnya ialah hubungan kebenaran dengan
fitrah seseorang.
Dalam bab v akan dibahas tentang kritik Murtaḍá Muṭahharī kepada Barat.
Barat yang dimaksud ialah pemikiran tentang kebenaran tokoh-tokoh populer seperti
Karl Marx, Descartes dan Comte. Ketiga tokoh ini banyak dikritik olehnya di
berbagai bukunya.
Sedangkan bab terakhir ialah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan
dari hasil penelitian yang penulis lakukan. Di samping itu juga berisi tentang saran
dan kritikan penulis terhadap hasil penelitian.
19
BAB II
TEORI KEBENARAN DARI BERBAGAI PANDANGAN
A. Model-model Kebenaran
Secara garis besar, kebenaran dapat disusun menjadi empat model yang
secara makna dan sumbernya berbeda. Di antaranya ialah kebenaran empiris,
kebenaran logis, kebenaran etis dan kebenaran metafisika.1
1. Kebenaran Empiris
Kata empiris sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu empeiria yang
berarti berpengalaman dalam, berkenalan dengan dan terampil untuk.2 Aliran
filsafat yang membahas tentang pengalaman disebut dengan empirisme.
Empirisme merupakan ide atau pengetahuan berasal dari pengalaman manusia.
Bagi aliran ini pengetahuan merupakan abstraksi dari berbagai pengalaman
manusia. Karena pengetahuan adalah abstraksi dari pengalaman, maka relasi
pengalaman dengan pengetahuan menjadi penentu kebenaran suatu pengetahuan.
Oleh karena itu kebenaran empirik dapat kita pahami sebagai kebenaran yang
dapat kita temukan pada level pengalaman empiris. Pengalaman empiris dapat
didefinisikan sebagai pengalaman yang kita temui dalam keseharian kita.
Kebenaran ini juga dapat dikatakan dengan kebenaran faktual. Faktual dalam
pengertian di sini adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan atau dijangkau oleh
pancaindra. Konsekuensi dari konsep kebenaran empirik mengakibatkan tidak satu
pun pengetahuan yang benar kecuali pengetahuan yang bersifat indrawi. Dalam
rangka membuktikan kebenaran pengetahuan, mau tidak mau ilmuwan harus
menyajikan bukti-bukti empiris yang dapat diverifikasi melalui pancaindra.3 Rasa
asin pada garam akan dikatakan sebuah pengetahuan yang benar hanya ketika rasa
asin pada garam tersebut dapat diuji melalui pengalaman langsung mengenai rasa
asin yaitu dengan cara mencicipi garam tersebut, jika garam rasanya memang asin
maka pengetahuan tentang garam asin dapat dibenarkan.
Memperkuat kuat argumen tentang kebenaran empirik, tokoh empirisme
John Lock mengatakan bahwa manusia dilahirkan dalam kondisi tidak mengetahui
apapun. Otak manusia kosong seperti kertas putih yang kosong yang belum terisi
apapun. John Lock mengistilahkan keadaan tersebut dengan tabula rasa (kertas
kosong).4 Kemudian dalam perjalanan hidupnya, manusia terus mendapatkan
pengetahuan melalui pengalaman-pengalaman empiris. Dari pengalaman indra
1 Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, Naturalistic Inquiry, (London: Sage
Publications, 1985), h. 14-15. Diakses pada Agustus 2019 dari
https://books.google.co.id/books?id=2oA9aWlNeooC&pg=PA14&lpg=PA14&dq=julienne+
ford+Lincoln+dan+Guba&source=bl&ots=0tpzX9S6wn&sig=ACfU3U1hFNRtXzpcXsuc1kj
_L05VWq-
fXw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjR_6OHzqDkAhWRiHAKHYyFBdYQ6AEwC3oECAk
QAQ#v=onepage&q=julienne%20ford%20Lincoln%20dan%20Guba&f=false 2 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 197.
3 Mahfud Junaedi, Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam, (Depok: Kencana,
2017), h. 33. 4 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 177.
20
itulah pengetahuan manusia didapatkan.5 Frederick Suppe mengatakan bahwa
dunia atau hal empiris merupakan awal mula dari terbentuknya proposisi. Maka
proposisi yang benar adalah proposisi yang benar-benar menegaskan secara
empiris tentang dunia.
Di sini lah tampak bahwa indra mempunyai posisi yang sangat penting
dalam mendapatkan pengetahuan, hingga ia dapat menentukan benar tidaknya
suatu pernyataan. Sedangkan batas-batas dari kebenaran empirik ini adalah sejauh
pancaindra mampu menunjukkan fakta empirisnya.6 Seandainya seseorang tidak
dapat menggunakan pengalaman indranya, maka ia tidak akan pernah sampai pada
kebenaran dari suatu pengetahuan. Seseorang tersebut tidak akan mendapatkan
pengetahuan yang benar. Semakin banyak pengalamannya maka semakin banyak
juga ia dapat membuktikan kebenaran suatu pengetahuan.
Bahkan bagi penganut kebenaran empirik kebenaran pengetahuan rasional
sekalipun seperti teori kausalitas, kebenarannya tidak dapat dikaji dan dibuktikan
oleh logika. Premis yang mengatakan bahwa semua manusia mati, Andi adalah
manusia. Jadi Andi pasti mati. Menurut kebenaran empiris tidak dapat dikatakan
benar begitu saja. Muḥammad tidak dapat digeneralisir premis pertama secara
tidak benar, sebab kita belum tahu apakah kematian berlaku bagi masing-masing
individu manusia seperti telah kita duga.7 Maka untuk membuktikan kebenarannya
ialah kita harus melihat bahwa memang Muḥammad adalah manusia yang mati.
Bagi penganut kebenaran empirik, teori kausalitas bukan berasal dari akal karena
akal tidak mampu menciptakan pengetahuan sendiri. Teori kausalitas merupakan
hasil dari pengalaman manusia, sehingga dalam menguji kebenarannya harus
dibuktikan secara empiris.8 Batu yang dilepaskan akan jatuh ke bawah. pernyataan
ini sebenarnya bukan berasal dari akal, tetapi berasal dari pengelaman manusia
yang melihat batu yang dilepaskan kemudian jatuh ke bawah. Di situlah
sebenarnya jika ingin membuktikan bahwa batu yang dilepaskan akan jatuh ke
bawah, maka seseorang harus melakukan percobaan. Dengan melakukan
percobaan, maka jelas kebenarannya. jika memang batu yang dilepaskan jatuh ke
bawah, maka pengetahuan tersebut benar adanya.
Penganut positivisme seperti Rudolf Carnap dan Moritz Schlick, bahkan
mengatakan dengan tegas bahwa hanya putusan-putusan ilmiah yang dapat
diverifikasi secara empiris yang dapat dianggap sebagai pengetahuan yang benar.
Karena untuk mengetahui kebenaran suatu putusan ilmiah harus menggunakan
metode verifikasi. Ketika putusan-putusan ilmiah telah diuji dengan kenyataan
yang dapat diamati oleh indra, dan ternyata putusan-putusan tersebut sesuai dengan
5 K. Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), h. 50.
6 Mukhtar latif, Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu, (Jakarta: Prenada
Media Group, 2016), h. 101. 7 Sayyid Muḥammad Bāqir al-Ṣadr, Falsafatunā. Penerjemah M. Nur mufid bin Ali,
(Bandung: Mizan, 1995), h. 41. 8 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum ...,h.183-184.
21
kenyataan yang ditangkap oleh indra, maka putusan itu sudah diverifikasi dan
kebenarannya sudah dikuatkan.9
Teori kebenaran empirik berdampak besar terhadap pengetahuan manusia.
Teori-teori non-indrawi selama ini yang banyak dianut oleh manusia menjadi salah
menurut pandangan empirisme, termasuk pengetahuan tentang agama. Teori-teori
yang disajikan oleh agama banyak pembahasan tentang sesuatu yang tidak tampak.
Ketika kita membahas tentang ilmu agama, tampaknya ilmuwan akan mengalami
kesulitan dalam membuktikan setiap teori yang terdapat dalam ajaran agama jika ia
menggunakan pendekatan empiris.
Kajian agama yang paling abstrak ialah kajian tentang Tuhan. Teori agama
mengatakan bahwa Tuhan adalah ada. Lalu bagaimana seseorang membuktikan
keberadaan Tuhan melalui pengalaman manusia sedangkan Ia begitu abstrak.
Dalam rangka menguji benar tidaknya pengetahuan tentang keberadaan Tuhan
menggunakan pendekatan kebenaran empirik, seseorang harus menunjukkan bukti-
bukti empiris mengenai keberadaan Tuhan berupa wujud Tuhan, tempat
tinggalNya dan pengalaman lain yang dapat dijangkau oleh indera. Jika seseorang
tidak dapat menunjukkan hal-hal empiris mengenai Tuhan, maka selama itu juga
pernyataan tentang “Tuhan ada” adalah salah. Keberadaan Tuhan menurut
kebenaran empiris tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga Tuhan dapat
dikatakan tidak ada. Maka tidak heran jika David Hume menolak tentang
keberadaan Tuhan.10
Jika agama dikaji menggunakan pendekatan kebenaran
empiri maka agama akan kehilangan sisi kebenarannya. Bahkan dampaknya,
manusia akan banyak kehilangan pengetahuan. Pengetahuan manusia tentang
agama dan pengetahuan metafisika lain yang sudah bertahan ribuan tahun akan
musnah begitu saja.
2. Kebenaran Logis
Kebenaran logis11
merupakan kebenaran yang didasarkan pada akal sehat
dan dibangun berdasarkan konstruksi argumen logika. Di sini terdapat syarat agar
pengetahuan yang dicapai oleh akal mampu mencapai kebenaran yaitu akal yang
sehat. Akal yang tidak sehat hanya akan mencapai kebenaran palsu, seperti cermin
rusak yang tidak akan mampu menampilkan objek dengan sebenar-benarnya.
Fahruddi Faiz12
mengatakan bahwa akal sehat berarti akal yang lurus, jujur dan
tidak memihak. Akal yang tidak sehat akan mengantarkan kita kepada
9 Muchamad Iksan, “Epistemologi Mencari Kebenaran Dengan Pendekatan
Transendental”, Proceeding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum,
April 2015, ISBN 978-602-72446-0-3, h. 34. 10
Ahmad Tafsir, Filsafat Umum ..., h.183. 11
Istilah logis berasal dari bahasa latin yaitu logos yang berarti perkataan atau
sabda. Di samping itu, logik juga berasal dari bahasa Yunani Kuno yang berarti logos yang
berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam
bahasa. Mukhtar Latif, Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu ..., h. 155. Lorens
Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 519. 12
Fahruddin Faiz adalah dosen filsafat Islam pada Prodi Aqidah dan Filsafat Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
22
pembenaran-pembenaran atau yang biasa kita sebut dengan rasionalisasi.13
Rasionalisasi adalah ketidakbenaran yang kemudian diberikan alasan-alasan
rasional sehingga pengetahuan itu tampak seakan-akan benar.
Kebenaran logis adalah persoalan apakah proses validasi berlangsung
sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir. Jadi kebenaran ini ditentukan oleh aturan-
aturan logika.14
Logika itu sendiri mengkaji hubungan antara pernyataan-
pernyataan yang berupa kalimat-kalimat atau rumusan-rumusan, sehingga dapat
ditentukan apakah suatu itu adalah benar atau salah. Dalam kajian logika, benar
tidaknya suatu pernyataan lebih mengarah kepada bentuk. Sedangkan kalimat yang
mempunyai nilai kebenaran disebut dengan proposisi. Proposisi hanya mempunyai
satu nilai kebenaran, yaitu benar atau salah dan tidak bisa keduanya.15
Proposisi, menurut logika tradisional Aristoteles, harus terdiri atas tiga
bagian, yaitu subyek, predikat, dan kopula. Kopula adalah suatu tanda yang
menyatakan hubungan di antara subyek dan predikat. Hubungan yang dinyatakan
oleh kopula mungkin berupa afirmasi (pembenaran), artinya kopula menyatakan
bahwa di antara subyek dan predikat memang terdapat suatu hubungan, dan
mungkin pula kopula menyatakan negasi (pengingkaran), artinya kopula
menyatakan bahwa antara subyek dan predikat tidak terdapat suatu hubungan
apapun.16
Contoh dari proposisi ialah “semua pencuri adalah penjahat”. Pada contoh
tersebut dapat ditentukan bahwa term semua “pencuri” adalah subyek, term
“penjahat” adalah predikat. Sedangkan term “adalah” merupakan kopula17
. Ketika
suatu proposisi telah terbukti benar, suatu kesimpulan baru yang sebelumnya tidak
diketahui. Proses ini disebut dengan penalaran.18
Contoh dari penalaran di
antaranya yaitu:
Semua pencuri adalah penjahat. (a adalah c) (Premis mayor)
Andi adalah pencuri. (b adalah a) (Premis minor)
Jadi Andi adalah penjahat. (b adalah c) (Konklusi)
13
Fakhruddin Faiz, Teori Kebenaran, video youtube ke-1 menit ke 25.48, 17
Desember 2015. Diakses pada 19 Juli 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=hCNvfg_4P-o 14
Y.P Hayon, Kesesatan Berpikir, (Surakarta: Tiga Pena Mandiri, 2012), h. 35. 15
Muhammad Rakhmat, Pengantar Logika Dasar, (Bandung: Logoz Publishing,
2013), h. 57. 16
Muhammad Roy Purwanto, Ilmu Mantiq, (Yogyakarta: Universitas Islam
Indonesia, 2019), h. 67. 17
Dalam sistem bahasa Inggris dan Arab, istilah kopula bisa berupa “to be” (is, are,
am) atau ẓamir (huwa, huma, hum dan seterusnya), sedangkan dalam tata bahasa Indonesia
kopula (seperti kata “adalah”) tidak begitu diperlukan karena pengertiannya sudah
terkandung dalam susunan subyek dan predikat. Misalnya proposisi “Ali adalah seorang
nelayan”, term “adalah” itu dapat dihilangkan dan tidak merubah arti. Akan tetapi dalam
pembahasan logika dengan pengantar bahasa Indonesia ini, kata “adalah” yang merupakan
kopula, harus tetap ditampilan demi menjaga persyaratan proposisi. Partap Sing Mehra dan
Jazir Burhan, Pengantar Logika, (Jakarta: Binatjipta, 1968), h. 34-5. 18
R.G. Soekadijo, Logika Dasar: Tradisional, Simbolik dan Induktif, (Jakarta:
Gramedia, 1985), h. 6.
23
Pada contoh di atas merupakan contoh penalaran yang terdiri dari tiga
proposisi, yaitu dua buah proposisi dasar dan satu buah proposisi yang
merupakan kesimpulan dari kedua proposisi awal. Proposisi kesimpulan
disebut konklusi dan dua proposisi dasar disebut dengan premis (premis
mayor dan minor). Tiap-tiap proposisi terdiri dari dua term, dan karena itu
silogisme meski mempunyai enam term. Namun pada dasarnya, ia hanya
terdiri dari tiga term, yang masing-masing diulang dua kali, yaitu term
mayor (major term), term minor (minor term), dan term tengah (middle
term), yang dilambangkan dengan M. Menurut Aristoteles, term mayor
adalah term yang menjadi predikat pada konklusi, sedangkan term minor
adalah term yang menjadi subyek pada konklusi. Selanjutnya, premis yang
terdapat term mayornya disebut premis mayor, dan premis yang terdapat
term minornya disebut premis minor.19
Pembahasan di atas merupakan suatu contoh penalaran yang tepat dan
menghasilkan kesimpulan yang tepat, karena susunan premis-premisnya sudah
dilakukan dengan tepat atau struktur proposisi dalam premis tetap. Meskipun
proposisi pada premis-premis adalah benar, namun ketika penyusunan tidak tepat
atau strukturnya berubah-ubah, maka dapat dipastikan kesimpulan yang dihasilkan
akan salah.20
Seperti susunan premis-premisnya salah meskipun setiap premisnya
benar, yaitu:
Semua pegawai negeri adalah penerima gaji. (benar)
Semua pegawai swasta adalah penerima gaji. (benar)
Jadi pegawai negeri adalah pegawai swasta. (salah)
Contoh penalaran salah yang disebabkan oleh struktur yang berubah ialah:
Ada puteri sala yang wanita luwes
R.S Ani adalah puteri sala
Jadi R.S Ani adalah wanita luwes
Bentuk kebenaran logis ini tidak memerlukan objek materi untuk
membuktikan kebenarannya, karena kebenaran dan kesalahan murni terdapat
dalam pikiran. Aturan-aturan logislah yang menjadi penentu kebenaran. Hal ini
dapat kita pahami bahwa nalar akal tampaknya dapat mengantarkan manusia pada
kebenaran yang pasti. 21
Lebih jauh dari itu, kebenaran logis dapat kita pahami
sebagai kebenaran yang masuk akal. Kebenaran yang dimaksud merupakan
pernyataan hipotesis yang secara logis atau matematis sejalan dengan pernyataan
lain yang telah diketahui sebagai suatu kebenaran.22
Jadi dalam kajian level
kebenaran ini, kekuatan proposisi dalam menentukan dirinya benar atau salah ialah
19
Muhammad Roy Purwanto, Ilmu Mantiq, (Yogyakarta: Universitas Islam
Indonesia, 2019), h. 71. 20
R.G. Soekadijo, Logika Dasar: Tradisional, Simbolik dan Induktif, (Jakarta:
Gramedia, 1985), h. 8. 21
Ahmad Zainul Hamdi, Tujuh Filsuf Muslim: Pembuka Pintu Gerbang Filsafat
Barat Modern, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 135. 22
A. Susanto, Filsafat Ilmu: Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis
dan Aksiologis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 89.
24
argumen-argumen rasional yang secara logis sangat kuat dan sudah diakui
sebelumnya sebagai suatu kebenaran. Kekuatan pengalaman atau benda-benda
fisik tidak menjadikan suatu pernyataan benar atau salah. Suatu pernyataan akan
tetap dianggap benar, meskipun tidak mempunyai bukti empiris berupa fakta-fakta
fisik. Fakta-fakta empiris seperti pengalaman manusia dan benda fisik lainnya
hanyalah menjadi penguat dari argumen-argumen logis. Suparlan mengatakan
bahwa kebenaran level ini merupakan kebenaran yang ditandai oleh adanya
gambaran yang jelas dan tegas tentang sesuatu itu dalam pikiran. Kebenaran ini
berprinsip bahwa kebenaran dapat ditangkap atau dikenal oleh akal karena adanya
kejelasan dan kepastian yang dihasilkan oleh kemampuan berpikir itu sendiri.23
3. Kebenaran Etik
Kebenaran etik adalah kebenaran yang berdasarkan etika. Landasan
kebenaran ini berbeda dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang
terpenting pada level kebenaran ini adalah kesesuaian suatu
pernyataan/prilaku/teori dengan norma-norma etis. Secara umum, norma-norma
etis terdapat dua bagian di antaranya ialah etika universal dan etika relatif/lokal.
Dengan demikian, kebenaran etik pun dapat dibagi dua, kebenaran etik universal
dan kebenaran etik lokal. Etika universal meyakini suatu nilai-nilai yang bersifat
konstan dan tidak terikat dengan syarat atau kondisi tertentu. Suatu tindakan dapat
dikatakan sebagai perilaku yang benar berdasarkan tolok ukur “keutamaan”.
Keutamaan memungkinkan manusia memilih perilaku yang tepat dan universal.24
Contoh dari etika universal di antaranya ialah membunuh sesama manusia. Dalam
tatanan kebenaran etik, perilaku membunuh tidak dapat dibenarkan karena
bertentangan dengan etika. Membunuh dalam kajian etika dilarang dan termasuk
prilaku yang buruk.
Level norma etika yang lain ialah etik relatif, yaitu suatu norma etika yang
tolok ukur kebaikan dan keburukannya bersesuaian dengan keadaan sosial pada
suatu tempat.25
Maka setiap suku tampaknya mempunyai kebenaran etik masing-
masing. Istilah lain ialah kebenaran etik merupakan kebenaran yang dihasilkan dari
hasil kesepakatan sosial. Orang Indonesia ketika bertemu dengan guru maka murid
harus mencium tangan, menunduk bahkan dalam memanggilnya harus
menggunakan bahasa yang halus dan sopan, perilaku seperti ini bagi orang
Indonesia dianggap benar. Tetapi berbeda dengan di Australia, di sana murid yang
mencium tangan, menunduk dan memanggil dosen menggunakan bahasa yang
halus dan sopan justru diyakini oleh gurunya sebagai murid yang ingin
menciptakan jarak dengan guru, maka perilaku tersebut dikatakan sebagai perilaku
yang salah. Satu perilaku yang sama tampaknya mempunyai sisi kebenaran yang
berbeda sesuai dengan wilayahnya. Kebenaran relatif ini akan mengalami
perubahan-perubahan sesuai dengan konteks dan kesepakatan-kesepakatan sosial
yang ada.
23
Suparlan Suhartono, Filsafat Ilmu Pengetahuan: Persoalan Eksistensi dan
Hakikat Ilmu Pengetahuan, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2005), h. 82. 24
K. Bertens, “Kata Pengantar” dalam Aristoteles, Nicomachean Ethics: Sebuah
Kitab Suci Etika. Penerjemah Embun Kenyowati, (Jakarta: Teraju, 2004), h. viii. 25
K. Bertens, Etika, (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 279.
25
Kebenaran ini didukung oleh filosof Barat yang mengatakan bahwa
sebenarnya kebenaran bukan tentang seberapa jauh subjek menangkap objek,
melainkan seberapa sesuai subjek dengan ranah praktis. Pandangan ini datang dari
penganut realisme. Mereka memandang realitas sebagai suatu yang bersifat plastis
atau berubah-ubah serta selalu mendapatkan pengaruh dari keadaan praktis seperti
ekonomi dan kultur.26
Maka teori kebenaran etis mempunyai pandangan yang
sejalan dengan teori ini bahwa kebenaran dapat kita lihat melalui etika yang bisa
jadi aturan-aturannya berbeda antara wilayah yang satu dengan yang lainnya.
Selain itu, kebenaran etika juga mengalami perubahan dari masa ke masa.
Fakta di masyarakat, nilai-nilai etika yang dilandaskan pada agama diakui sebagai
kebenaran dan diterapkan dalam kehidupan. Bagi muslim Indonesia misalnya,
berboncengan dengan lawan jenis di luar nikah diakui sebagai kesalahan dalam
bergaul antara pria dan wanita. Pengakuan tersebut berlandaskan pada nilai-nilai
etika keagamaan. Fenomena ini terwujud dalam fakta di masyarakat yang dapat
diamati dalam kehidupan sehari-hari pada era pra globalisasi.
Sebaliknya, di era globalisasi nilai-nilai kebenaran khususnya kebenaran
etika bergaul dan berpakaian antara pria dan wanita menurut Islam sudah mulai
ditinggalkan oleh sebagian anggota masyarakat remaja yang terwujud dalam fakta.
Sebagai contoh ajaran Islam (larangan mendekati zina) sebagai suatu ajaran yang
mengandung nilai kebenaran mutlak, kini telah ditinggalkan oleh sebagian remaja
yang berpola pikir kebarat-baratan. Islam juga mengajarkan nilai sopan santun
yang mengandung nilai kebenaran tentang keharusan kaum wanita untuk menutup
aurat, namun dalam faktanya, sebagian remaja kita telah menganggap ajaran itu
tidak benar atau kuno, sehingga mereka berpakaian sangat seksi. Karena itu dapat
disimpulkan bahwa nilai kebenaran agama mengalami krisis dan kesenjangan
dengan kenyataan atau fakta yang diamati dalam kehidupan sehari-hari di
masyarakat.
4. Kebenaran Metafisik
Ibn Rushd mendefinisikan metafisika sebagai pengetahuan tentang wujud.
Metafisika adalah bagian dari ilmu teoritis. Ia mempelajari kemaujudan secara
mutlak; prinsip nonbendawi hal-hal fisis yang dapat dirasakan seperti kesatuan,
kemajemukan, kemampuan, aktualisasi dan sebagainya; sebab-sebab segala yang
ada di samping Tuhan dan wujud-wujud suci. Jadi metafisika mempelajari tentang
sebab-sebab tertinggi dari hal tertentu yang jauh melampaui jangkauan indra.27
Kebenaran metafisik merupakan kebenaran tentang hal-hal di balik dunia
fisik. Maka kebenaran dalam versi ini menggali suatu kebenaran yang tidak dapat
dijangkau secara logis dan empiris. Kajian logika dan empiris hanya mampu
mencapai kebenaran-kebenaran terbatas. Kebenaran logis hanya sampai pada
kebenaran sejauh kemampuan akal menjangkau. Sedangkan akal tidak dapat
mencapai seluruh realitas wujud. Ada sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh
26
Akhyar Yusuf Lubis, Paradigma Positivisme dalam Epistemologi Pasca
Positivisme, dalam Heraty Noerhadi, Berpijak Kepada Filsafat: Kumpulan Sinopsis
Disertasi Program Pascasarjana Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas
Indonesia, (Depok: Komunitas Bambu, 2013), h. 317-318. 27
MM Syarif, Para Filosof Muslim, (Bandung: Mizan, 1996), h. 226.
26
perantara rasional bahkan silogisme rasional sendiri pada saat tertentu tidak bisa
menjelaskan atau mendefinisikan sesuatu yang diketahuinya.28
Sedangkan
kebenaran empiris hanya mencapai kebenaran yang sifatnya pengalaman
keseharian melalui pancaindra. Kedua kebenaran itu oleh pengikut metafisika
dianggap sebagai kebenaran nisbi, karena kebenaran selain yang metafisik
hanyalah bayangan yang terus berubah-ubah. Kebenaran yang hakiki bagi para
metafisika ialah kebenaran di balik materi dan jangkauan akal.
Bagi Suhrawardi pengetahuan yang kebenaran merupakan pengetahuan
yang dipahami subjek yang dilihat secara langsung tanpa penghalang apapun.
Menurutnya objek dapat dipahami secara valid hanya ketika subjek merasakan
langsung tentang objeknya.29
Agar sesuatu dapat diketahui, sesuatu harus dilihat
seperti apa adanya, sehingga pengetahuan yang diperoleh memungkinkannya
untuk tidak butuh definisi. Misalnya warna merah. Warna merah hanya bisa
diketahui jika terlihat seperti apa adanya dan sama sekali tidak bisa didefinisikan
oleh dan untuk orang yang tidak pernah melihat sebagaimana adanya.
Sebuah pengetahuan yang benar hanya bisa dicapai lewat hubungan
langsung tanpa halangan antaran subjek yang mengetahui dengan objek yang
diketahui. Teori ini sekaligus membantah teori para ilmuwan sebelumnya yang
mengatakan bahwa kebenaran merupakan kesesuaian antara konsepsi dengan
realitas objek, karena objek adalah independen dan terpisah dengan subjek. Namun
pemikiran tentang kebenaran korespondensi menurut Suhrawardī mempunyai
kelemahan-kelemahan di antaranya ialah teori kebenaran tersebut tidak dapat
mencapai kebenaran dikarenakan kedua kebenaran tadi menunjuk pada sesuatu
yang tidak hadir, objeknya menjadi terbatas karena tidak semua objek bisa
dikonsepsikan atau didefinisikan, validitasnya tidak terjamin karena apa yang ada
dalam konsep mental ternyata tidak pernah identik dengan realitas objektif yang
ada di luar pikiran dan terikat pada ruang dan waktu.30
Bahkan Karen Armstrong dalam buku tentang Sejarah Tuhan mengatakan
bahwa kebenaran tertinggi berupa kebenaran Tuhan menurutnya tidak dapat
diungkap dalam kata-kata maupun konsep. Kebenaran Ilahi hanya didapatkan
melalui pewahyuan kepada kita melalui pengalaman. Kebenaran puncak dari
metafisika tidak dapat digambarkan melalui kata-kata dan tidak dapat dipikirkan
oleh akal, akan tetapi sesuatu yang dengannya kata-kata diucapkan dan sesuatu
yang dengannya akal berpikir. Mustahil untuk berbicara kepada Tuhan yang
semalaikat ini atau berpikir mengenai dia, menjadikannya objek pikiran semata. Ia
adalah realitas yang hanya bisa dicerna dalam puncak perasaan orisinal yang
melampaui kesadaran diri.31
Kebenaran dalam versi ini menurut Haidar Baqir
adalah kebenaran pasti dan otoritatif, namun kebenarannya tidak berlaku bagi
28
H.A Khudori Soleh, Filsafat Islam: Dari Klasik Hingga Kontemporer,
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 139. 29
H.A Khudori Soleh, Filsafat Islam ..., h. 148-149. 30
H.A Khudori Soleh, Filsafat Islam ..., h. 148. 31
Karen Armstrong, Sejarah Tuhan: Kisah 4.000 Tahun Pencarian Tuhan dalam
Agama-Agama Manusia. Penerjemah Zaimul Am, (Bandung: Mizan, 2011), h. 68.
27
orang-orang yang berada di luarnya. Keadaan tersebut hanya bisa ditangkap hanya
oleh orang-orang yang mengalaminya.32
Dalam rangka menemukan kebenaran, teori kebenaran metafisika juga
mempunyai teori kehadiran. Di mana kebenaran merupakan kehadiran objek pada
subjek. Ketika objek sudah hadir dalam diri subjek, sejak itulah sesungguhnya
suatu konsep tidak diperlukan suatu pengujian kesesuaian. Karena antara objek dan
subjek sudah bersatu dalam subjek.33
Dalam rangka membuktikan kebenaran ini
sesungguhnya tidak memerlukan perantara apapun, baik indra maupun akal.
Kebenaran dalam bentuk ini sesungguhnya merupakan kebenaran yang pasti dan
hakiki, karena subjek langsung menyatu dengan objek yang memang hadir dalam
subjek. Maka teori korespondensi maupun koherensi yang digaungkan oleh para
filosof dan saintis Barat, pada pengetahuan ini tampaknya tidak berlaku.
Puncak kebenaran metafisik ini ialah suatu eksistensi yang hakiki,
kebenaran wujud Ilahi yang pasti dan tidak berubah. Kebenaran-kebenaran
semacam ini merupakan kebenaran hakiki yang langsung dilimpahkan oleh Yang
Maha Suci ke dalam jiwa seseorang.34
Oleh karena itu, kebenaran versi ini adalah
kebenaran yang tidak mungkin tidak benar. Kebenaran gaib ini, memang tak
terkatakan dan tidak dapat dijelaskan, namun dapat dimiliki oleh orang yang
hatinya suci. Kebenaran pada teori metafisika selalu mempersepsikan dirinya yang
terbaik, berada pada keabadian yang tidak pernah berakhir. Hakikat atau kesejatian
adalah bentuk lain dari eksistensi Tuhan. Hakikat kebenaran agama adalah fitrah
yang tidak terpisahkan dengan keberadaan Tuhan sebagai sumber dari kebenaran.
Kesejatian merupakan kebenaran yang hakiki, senantiasa terhubung kepada Sang
Pencipta. Agama pasti bersumber dari yang Maha Benar.
B. Berbagai Macam Teori Kebenaran
Perdebatan tentang teori kebenaran di Barat berkembang cukup baik.
Perkembangan itu ditandai oleh lahirnya banyak teori kebenaran yang tiap teori itu
mempunyai karakteristik yang unik. Secara garis besar, teori kebenaran Barat dapat
kita klasifikasikan dalam beberapa kategori, di antara aliran yang dimaksud ialah
teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatis.35
1. Teori Kebenaran Korespondensi
Teori kebenaran korespondensi merupakan teori yang cukup tua
dibandingkan teori-teori lainnya seperti materialisme, pragmatisme dan lainnya.
Bahkan Philip T. Dunwoody mengatakan teori ini merupakan teori kebenaran
32
Haidar Baqir, Epistemologi Tasawuf: Sebuah Pengantar, (Bandung: Mizan,
2017), h. 18. 33
Zaprulkhan, Filsafat Islam: Sebuah Kajian Tematis, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2014), h. 135-136. 34
Ahmad Baiquni dan Azam Bakhtiar, Epistemologi Tasawuf: Sebuah Pengantar,
(Bandung: Mizan, 2017), h. 62, 35
Zamrulkhan, Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer, (Jakarta: Raja
Grafindo, 2016), h. 107.
28
tertua.36
Unsur-unsur teori ini sudah ada pada zaman sebelum Masehi, yaitu sejak
filosof Heraklitus (535-475 SM). Kemudian diteruskan oleh Aristoteles (384-322
SM), juga tampak dalam pandangan Thomas Aquinas dan didukung oleh para filsuf
Inggris sejak abad pertengahan pada waktu pencerahan.37
Aristoteles menekankan
pentingnya pengamatan terhadap pemahaman kita tentang fenomena alam dan
memberikan definisi korespondensi yang berpendapat bahwa pernyataan atau
proposisi yang benar mencerminkan realitas itu sendiri.38
Bahwa sesuatu yang benar
itu adalah sesuatu yang menunjukkan objek apa adanya. Kalimat Aristoteles yang
terkenal ialah “To say of what is that it is not, or of what is not that it is, is false,
while to say of what is that it is, and of what is not that it is not, is true”.39
Maka
kepercayaan kita perlu sesuai dengan kenyataan dan juga tidak bertentangan dengan
diri sendiri, karena kita mengalami satu realitas.
Para peneliti seperti Jamin Asay mendefinisikan teori kebenaran
korespondensi sebagai suatu teori yang menjadikan fakta sebagai penentu
kebenaran. Dalam pandangan korespondensi, sesuatu dapat dikatakan sebagai benar
ketika ia mempunyai relevansi atau kesesuaian dengan fakta-fakta.40
Pengetahuan
seseorang akan benar manakala apa yang diketahuinya merujuk kepada objek atau
realitas tertentu. Dengan demikian kebenaran adalah kesesuaian antara pengetahuan
dengan fakta yang sebenarnya tentang apa yang diketahui. Dalam teori
korespondensi antara pengetahuan dan fakta seharusnya terdapat kesamaan. Jika
sesuatu tersebut tidak mempunyai fakta, maka sejak itu pula sesuatu itu salah.41
Tidak salah ketika kita mengatakan bahwa kebenaran merupakan ungkapan tentang
realitas objek apa adanya.
Posisi manusia terhadap teori kebenaran ini adalah sebagai subjek
penangkap konsepsi fakta. Fakta atau realitas ditangkap oleh manusia kemudian
dikelola pikiran. Di situlah awal mula terbentuknya konsep atau pengetahuan. Maka
pada hakikatnya pengetahuan atau konsep merupakan abstraksi dari apa yang ada di
dunia. Pikiran pada teori ini hanyalah sebatas menerima pengetahuan dari objek.
36
Philip T. Dunwoody, “Theories of Truth as Assessment Criteria in Judgment and
Decision Making”, dalam Judgment and Decision Making, vol. 4, no. 2, March 2009, h. 117. 37
C. Verhaak dan Haryono Iman, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Telaah Atas Cara
Kerja Ilmu-ilmu, (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 122-123. 38
Neal V. Dawson, “Correspondence and Coherence in Science: A Brief Historical
Perspective”, dalam Judgment and Decision Making, vol. 4, no. 2, March 2009, h. 126-133.
Diakses pada 01 Agustus 2019 dari http://journal.sjdm.org/ccdg/ccdg.html. 39
Dr Chris Henry, “The Politics of (Post) Truth: Theories of Truth in Contemporary
Philosophy”, h. 2. Diakses pada 20 Agustus 2019 dari
https://www.cumberlandlodge.ac.uk/sites/default/files/public/The%20Politics%20of%20%28
Post%29%20Truth%20-%20Philosophy%20Resources.pdf 40
Jamin Asay, The Primitivist Theory of Truth, (New york: Cambridge University
Press, 2013), h. 12. Diakses dari
https://books.google.co.id/books?id=3VICAQAAQBAJ&pg=PA12&dq=Theories+of+Truth
&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi3z9K43I3iAhUIXisKHYLpAXYQ6AEITDAG#v=onepage
&q=Theories%20of%20Truth&f=false. 41
J. W. Gercke dkk, “Philosophical Theories of Truth and The Logical Status of
Intra-Biblical Fallacies of Contextomy”, in Jurnal In Die Skriflig, vol. 43, no. 4, 2009, h.
784.
29
Pikiran tidak dapat membuat pengetahuan sendiri, karena tanpa fakta pengetahuan
yang benar tidak akan terwujud. Oleh karena itu, objek nyata menjadi penentu benar
tidaknya suatu pengetahuan.
Fakta dapat kita pahami sebagai hal-hal yang bersifat duniawi, sebagaimana
dijelaskan oleh Hamdani.42
Panca Indra merupakan alat yang digunakan untuk
menangkap suatu fakta. Fakta-fakta yang dialami langsung oleh pancaindra, kita
sebut sebagai fakta empiris.43
Madura merupakan salah satu pulau yang berada di
Jawa Timur adalah fakta. Bola jatuh dari atas ke bawah adalah fakta. Matahari terbit
adalah fakta. Fakta merupakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dan dapat
dialami oleh indra. Karena pengetahuan hanya didapatkan dari fakta-fakta maka,
pengamatan, percobaan atau pengujian empiris menjadi penting dalam menguji
kebenaran suatu pengetahuan dalam rangka mengungkap fakta yang sesungguhnya.
Metode dalam mencapainya disebut metode observasi. Pengetahuan yang terungkap
hanya melalui dan setelah pengalaman dan percobaan empiris.44
Tanpa dapat
dibuktikan secara empiris, maka pengetahuan tersebut adalah salah.
Dampak dari teori ini adalah seluruh proposisi, pernyataan atau pengetahuan
sebaik apapun jika tidak dapat menunjukkan suatu fakta empiris, maka pernyataan
itu tidak dianggap sebagai kebenaran bahkan pernyataan itu tidak dinamakan
pengetahuan melainkan hanya sebatas keyakinan. Keyakinan tidak dapat
dikategorikan sebagai pengetahuan karena tidak dapat diuji secara empiris. Misalkan
pernyataan tentang wanita baik akan dikatakan sebagai pernyataan yang benar dan
ilmiah hanya ketika pernyataan itu diikuti oleh bukti-bukti yang menunjukkan
bahwa wanita tersebut adalah baik. Berdasarkan gagasan di atas dapat kita pahami
bahwa pengetahuan/pernyataan merupakan potret dari realitas yang ada di dunia.
Semakin lengkap suatu pengetahuan menggambarkan suatu realitas dunia, maka
semakin benar teori tersebut. Fakta sentris dalam penentuan kebenaran ini
dipengaruhi oleh para empirisme yang memang dalam mengkaji pengetahuan
menggunakan korespondensi.
Richard L. Kirkham, seorang profesor filsafat di Georgia State University
membagi teori korespondensi menjadi dua bagian yaitu korespondensi sebagai
korelasi dan korespondensi sebagai kongruensi.45
Pertama, korespondensi sebagai
korelasi merupakan pandangan yang mengatakan bahwa setiap pembawa
kebenaran46
adalah berkorelasi dengan sebuah keadaan. Jika keadaan yang
dikorelasikan dengan sebuah pembawa kebenaran benar-benar mewujud, maka
pembawa kebenaran adalah benar, kalau tidak ia adalah salah. Sebuah pembawa
kebenaran secara keseluruhan berkorelasi dengan sebuah keadaan secara
keseluruhan. Kedua, korespondensi sebagai kongruensi yang menyatakan bahwa
42
Hamdani, Filsafat Sains, (Bandung, Pustaka Setia, 2011, h. 40. 43
Jujun S. Suria Sumantri, Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan
tentang Hakikat Ilmu, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 5. 44
A. Sonny Keraf dan Mikchael Dua, Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan
Filosofis, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 67. 45
Richard L. Kirkham, Teori-Teori Kebenaran. Penerjemah M. Khozim, (Bandung:
Nusa Media, 2013), h. 179. 46
Pembawa kebenaran seperti proposisi, kalimat atau apa pun yang dipandang
sebagai pembawa kebenaran.
30
terdapat keserupaan struktural antara pembawa kebenaran dan fakta-fakta yang
mereka korespondensikan ketika pembawa kebenaran adalah benar. Ia mengatakan
bahwa struktur keyakinan seperti proposisi dan lainnya mencerminkan atau
menggambarkan struktur fakta dengan cara-cara sebagaimana sebuah peta
mencerminkan struktur bagian-bagian dunia yang dipetakannya.47
Meskipun teori ini banyak digunakan masyarakat dalam menentukan
kebenaran dalam hidupnya, akan tetapi teori ini mempunyai kelemahan yang
mendasar. Thomas Kuhn misalnya mengatakan bahwa kebenaran sebenarnya tidak
dapat dikatakan sebagai kesesuaian antara pengetahuan/teori dengan realitas karena
menurutnya setiap pengetahuan/teori dipengaruhi oleh paradigma yang dianut
subjek. Subjek yang berbeda dalam memandang realitas yang sama tampaknya tidak
dapat dibandingkan, karena realitas akan dipahami berbeda sesuai dengan paradigma
subjek dan situasi pada waktu subjek menangkap realitas. Objek yang sama akan
melahirkan nilai yang berbeda ketika situasi dan keadaan tempat objek diteliti.
Demikian juga dengan teori, teori akan dinilai berbeda oleh subjek yang berbeda
ditambah pula dengan perbedaan situasi dan kondisi di mana teori tersebut diuji.48
Kuhn juga membantah teori gagasan korespondensi tentang “kebenaran
alam dapat diketahui oleh manusia”. Albert Einstein (1879-1955 M) mengklaim
bahwa alam semesta pasti dapat dimengerti oleh manusia dan dapat dirumuskan
dalam suatu teori yang menjadi pengetahuan. Tuhan tidak akan menciptakan alam
semesta yang tidak dapat dipahami. Namun kendala yang dialami manusia adalah
bahwa untuk dapat mengerti sepenuhnya tentang alam, manusia mengalami
kesulitan. 49
Namun teori-teori semacam yang dikatakan oleh Einstein tidak mungkin
seseorang capai. Teori pada dasarnya hanyalah bentuk memodelkan realita menjadi
suatu dugaan terhadapnya. Maka teori sebenarnya tidak pernah sampai pada realitas
dan tidak pernah sebangun dengan realitas. Sehingga menjadikan kesesuaian antara
pengetahuan dengan realitas adalah bentuk kemustahilan nyata.50
Jika kita
menggunakan ukuran kesesuaian ini sebagai landasan kebenaran maka kebenaran
tidak akan pernah dicapai.
Selain itu kritikan berikutnya ialah mengenai hakikat fakta yang dijadikan
landasan. Faktanya pancaindra yang dijadikan sandaran utama oleh teori ini
mempunyai banyak kelemahan-kelemahan. Pernyataan tentang ukuran “bintang
sangat besar” ketika dibuktikan secara empiris bintang menampakkan diri kepada
mata manusia sebagai benda kecil yang bercahaya. Padahal pada hakikatnya bintang
sangat besar, hanya jarak yang jauh membuat bintang tampak kecil. Di sinilah
tampaknya teori korespondensi mengalami permasalahan. Teori korespondensi
47
Richard L. Kirkham, Teori-Teori Kebenaran ..., h. 180. 48
Frederick Suppe, “Facts An Empirical Truth, Canadian Journal of Philoshophy”,
Vol. iii, No. 2, Desember 1973, h. 197. 49
Neal V. Dawson, “Correspondence and Coherence in Science: A Brief Historical
Perspective”, in Jurnal Judgment and Decision Making, vol. 4, no. 2, March 2009. Diakses
pada tanggal 01 Agustus 2019 dari http://journal.sjdm.org/ccdg/ccdg.html. 50
Eko Wijaya, Evolusi Kebudayaan Menurut Richard Dawkins, dalam Toeti Heraty
Noerhadi, Berpijak Kepada Filsafat: Kumpulan Sinopsis Disertasi Program Pascasarjana
Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, (Depok: Komunitas
Bambu, 2013), h. 219-220.
31
tampaknya tidak selamanya menyajikan kebenaran. Ternyata ada proposisi-proposisi
yang tidak dapat dijangkau oleh teori korespondensi. Oleh karena itu, teori
korespondensi kemudian mendapat kritikan dari kaum rasionalis yang kemudian
melahirkan teori kebenaran koherensi.
2. Teori Kebenaran Koherensi
Kata koherensi dalam bahasa Inggris ialah coherence yang mengandung arti
sticking together, consistent (especially of speech, thought, reasoning), clear, easy
to understand. Sedangkan dalam bahasa Latin kata koherensi ialah cohaerere yang
berarti melekat, tetap menyatu, bersatu.51
Istilah koherensi dapat kita artikan sebagai
suatu hubungan yang terjadi disebabkan oleh adanya gagasan (prinsip, relasi, aturan,
konsep) yang sama.52
Teori kebenaran koherensi merupakan teori kebenaran yang
menjadikan suatu konsep atau aturan rasional sebagai tolok ukur kebenaran.
Sedangkan tokoh pengembang awal teori koherensi menurut Jujun adalah
Aristoteles dan Plato.53
Hal tersebut yang kemudian menyebabkan teori ini menjadi sangat berbeda
dengan teori korespondensi yang telah dijelaskan sebelumnya. Teori korespondensi
menjadikan realitas sebagai tolok ukur kebenaran, sedangkan teori koherensi tidak
menjadikan realitas materi sebagai tolok ukur kebenaran. Teori kebenaran koherensi
bisa dikatakan sebagai teori kebenaran yang berlevel kebenaran logik54
, yaitu suatu
kebenaran yang berdasarkan kaidah-kaidah logika. Teori ini juga dapat disebut
dengan teori logis. Logika dijadikan sebagai landasan ilmu oleh para ilmuwan
setelah Aristoteles. Bahkan Poerwantana mengatakan bahwa logika menjadi mutlak
bagi seseorang untuk mencapai kebenaran.55
Ia mengatakan begitu karena hal-hal
yang logis kebenarannya lebih pasti dan tidak berubah-ubah dibandingkan dengan
teori kebenaran lain. Pengetahuan yang benar menurut teori ini adalah pengetahuan
yang mempunyai relasi yang sudah ada. Maka sesungguhnya, pernyataan, teori atau
pengetahuan dianggap benar kalau sejalan dengan pernyataan, teori atau
pengetahuan yang sudah ada dan kebenarannya sudah diuji. Dengan kata lain, jika
proposisi tersebut sejalan, meneguhkan dan konsisten dengan teori yang sudah benar
sebelumnya.56
Pernyataan akan dianggap benar jika ia mempunyai kesesuaian atau
51
Peter L. Angles, A Dictionary of Philosophy, (London: Harper & Row Publishers,
1981), h. 40; lihat juga Lorenz Bagus, Kamus Filsafat ..., h. 470. 52
Peter L. Angles, A Dictionary of Philosophy ..., h. 40; lihat juga Lorenz Bagus,
Kamus Filsafat ..., h. 470. 53
Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, cet. ke-20,
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014), h. 57. 54
Sedangkan pemikiran tentang logos universal pertama kali digagas oleh
Heraclitus. Teori ini cukup populer dan menjadi perbincangan sejak pada masa Aristoteles
karena memang teori logika dirumuskan dengan baik oleh Aristoteles. Teori logika ini awal
mulanya berasal dari buku Aristoteles yang berjudul “Organon” yang kemudian menjadi
landasan ilmu logika berikutnya. Poerwantana Dkk, Seluk-Beluk Filsafat Islam, (Bandung,
PT Remaja Rosdakarya, 1994), h. 25-26. 55
Poerwantana Dkk, Seluk-Beluk Filsafat Islam, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya,
1994), h. 25-26. 56
A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan Filosofis,
h. 68.
32
konsisten dengan kaidah-kaidah logika atau pernyataan yang sebelumnya sudah
diakui kebenarannya.57
Dengan begitu teori ini juga disebut dengan istilah the
consistence theory of truth.58
Kebenaran model ini biasanya dipakai dalam menentukan kebenaran
matematika. Penjumlahan 2+2 = 4 adalah benar sesuai dengan teori matematika.
Penjumlahan ini tidak membutuhkan bukti empiris. Kalaupun terdapat 2 sapi + 2
sapi = 4 sapi. Tambahan sapi di sana hanyalah penguat dan tidak mengubah status
kebenaran penjumlahan tersebut. Hal yang membuat salah suatu pernyataan ialah
ketika tidak konsisten dengan sebelumnya yang dianggap benar contohnya ketika
2+2 = 5. Dalam teori kebenaran ini, hubungan antara pernyataan dengan realitas
tidak lagi menjadi suatu pernyataan benar atau salah, tetapi hubungan antara
pernyataan dengan pernyataan sebelumnyalah yang menjadikannya benar atau
salah.59
Jadi kebenaran koherensi menerangkan bahwa kebenaran merupakan
kesesuaian suatu pernyataan dengan pernyataan lain yang sudah lebih dahulu
diketahui, diterima dan diakui sebagai kebenaran dan ia merupakan sebuah
keputusan akan dianggap benar oleh teori ini jika mendapat penyaksian dari putusan
lain yang lebih dulu sudah diketahui, diterima dan diakui kebenarannya.60
Amsal
Bakhtiar menambahkan bahwa teori ini juga dapat dinamakan sebagai teori
penyaksian (justifikasi) tentang kebenaran, karena satu putusan dianggap benar
apabila mendapat penyaksian-penyaksian (pembenaran) oleh putusan-putusan
lainnya yang terdahulu yang sudah diketahui kebenarannya.61
Namun menurut Bochenski dalam buku Suparlan Suhartono menerangkan
bahwa kebenaran teori koherensi justru terletak pada adanya kesesuaian antara suatu
benda atau hal dengan pikiran atau idea.62
Inilah yang disebut dengan kebenaran
ontologis. Yaitu kebenaran yang tolok ukurnya berada pada dunia idea. Teori ini
memang dibuat oleh para filosof idealisme yang pada doktrin dasar mengatakan
bahwa kebenaran hakiki hanyalah kebenaran idea yang tidak pernah berubah.
Sehingga tidak heran ketika idea dijadikan landasan kebenaran pada teori ini. Idea
sebagaimana kita ketahui dari Plato, merupakan kebenaran yang hakiki karena
bentuknya yang tidak berubah-ubah sehingga kepastian kebenaran dapat
dipertanggung jawabkan. Suatu contoh ialah kucing yang benar bukanlah kucing
partikular yang kita lihat, kucing yang benar adalah kucing yang ideal, yang abstrak,
yang merupakan substansi universal dari semua kucing yang ada. Kucing yang
tampak pada manusia hanyalah kucing partikular yang merupakan gambaran atau
citra atau perwujudan dari yang ideal, maka kucing partikular adalah kebenaran
57
Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer ..., h. 57. 58
Endang Saifuddin Anshari, Ilmu Filsafat dan Agama, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,
1987), h. 23. 59
Ahmad Atabik, “Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu: Sebuah Kerangka
Untuk Memahami Konstruksi Pengetahuan Agama”, dalam Fikrah, Vol. 2, No. 1, Juni 2014, h.
260. 60
Biyanto, Filsafat Ilmu dan Ilmu Keislaman, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),
h. 161. 61
Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, (Jakarta: Rajagrafindo Press, 2012), h. 117. 62
Suparlan Suhartono, Filsafat Ilmu Pengetahuan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,
2008), h. 84.
33
palsu.63
Kucing pada dunia materi dapat dikatakan benar sebagai kucing manakala ia
sesuai dengan realitas aslinya, yaitu idea tentang kucing. Demikian juga teori-teori
logika yang oleh para filosof dikatakan sebagai ilmu pasti yang sangat meyakinkan.
Plato dan Aristoteles adalah dua tokoh yang mengembangkan teori koherensi awal
yang kemudian digunakan dalam menyusun ilmu ukur oleh Euclid.64
Untuk
selanjutnya teori koherensi digunakan oleh kaum idealis seperti FH. Bradly (1846-
1924 M).
Ada yang menarik dalam buku yang disajikan oleh C. Verhaak S.J. Ilmu
logika yang selama ini diyakini oleh banyak orang sebagai ilmu yang pasti, justru ia
buktikan sebagai salah satu bagian dari ilmu yang nisbi. Teori aksioma sistem yang
dikembangkan oleh Euklides65
justru mendapatkan bantahan dari Girolami Saccheri
(1667-1733
M). Girolami pada akhirnya mampu membuktikan kesalahan teori
Euklides. Teori Euklides mengatakan bahwa jumlah sudut ketiga sudut segi tiga
ialah 180 derajat, namun oleh Girolami Saccheri66
dapat dibuktikan dengan dua
bentuk hasil penelitian. Di antaranya ialah pertama ialah bahwa jumlah ketiga sudut
segi tiga adalah kurang dari 180 derajat. Sedangkan bentuk kedua ialah jumlah
ketiga sudut segi tiga tersebut ialah kurang dari 180 derajat. Ternyata keduanya
berhasil mengembangkan suatu ilmu ukur tanpa kontradiksi.67
Pembuktian
kekeliruan dari teori matematika awal tersebut merupakan bukti kenisbian atau
63
Bertrand Russel, Sejarah Filsafat Barat. Penerjemah Wajiz Anwar, (Yogyakarta:
Yayasan al-Jami‟ah, 1968), h. 70. 64
Nurani Soyomukti, Pengantar Filsafat Umum: dari Pendekatan Historis,
Pemetaan Cabang-Cabang Filsafat, Pertarungan Pemikiran, Memahami Filsafat Cinta,
hingga Panduan Berpikir Kritisi Filosofis, (Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2016), h. 175. 65
Euklides merupakan matematikawan yang lahir di Alexandria, Mesir. Alexandria
juga disebut dengan istilah Iskandariyyah. Tahun lahir dan meninggalnya belum diketahui
pasti, tetapi ia dikabarkan hidup sekitar abad ke-4 SM. Secara spesifik, Euklides disebut
sebagai bapak geometri karena ia telah mengemukakah teori bilangan dan geometri yang
cukup berpengaruh pada ilmuwan sesudahnya. Diakses dari http://journal-sport-
q.lautan.info/id4/800-685/Euklides_22880_stikom-bali_journal-sport-q-lautan.html 66
Girolami Saccheri merupakan matematikawan asal Italia. Ia dianggap sebagai
ilmuwan yang karyanya dianggap sebagai buku pertama dalam geometri non-Euclid. Namun,
pada abad ke-18 ia diketahui sebagian besar karyanya merujuk kepada tulisan Naṣīr al-Dīn
(1201-1274 M). Naṣīr al-Dīn adalah matematikawan muslim ternama Persia yang menjadi
pengikut dan komentator Omar Khayyām (1048-1131 M). Melihat kerangka di atas, maka
Omar Khayyām dianggap sebagai pelopor bagi Girolami Saccheri dalam meletakkan dasar
geometri non-Euclid. Maka ilmuwan yang pertama mengkritik Euklides/Euclid bukanlah
Girolami, melainkan ʻUmar Khayyam. ʻUmar Khayyam adalah matematikawan, astronom
sekaligus penyair. Ia menulis lebih dari 2000 buku. Salah satu kontribusi terbesar Khayyam
dalam matematika tentang geometri tertuang dalam bukunya yang berjudul “Fī Sharkma
Ashkālā min Muṣādarat Kitāb Uqlidis”. Dalam buku I risalahnya, Omar mengkritik teori
Euclid tentang garis sejajar, sedangkan dalam buku II dan III, dia menghubungkan dengan
teori perbandingan dan ukuran. Muchammad Abrori, “Matematikawan Muslim Terkemuka”,
dalam Kaunia IV, no. 2 Oktober 2008, h. 214. Review buku Mohaini Mohamed,
Matematikawan Muslim Terkemuka, (Jakarta: Salemba Empat, 2001). 67
C. Verhaak S.J dan Haryono Imam, Filsafat Ilmu Pengetahuan, (Jakarta:
Gramedia, 1991), h. 87-89.
34
ketidakpastian ilmu pasti. Bahwa logika pada dasarnya merupakan ilmu yang juga
tidak dapat mencapai kepastian mutlak. Logika yang diklaim sebagai satu-satunya
ilmu pasti ternyata terdapat celah-celah yang dapat meruntuhkan kepastiannya,
sehingga posisi teori ini sama seperti kenisbian teori lainnya. Demikian ungkap C.
Verhaak dan R. Haryono Imam.
Perbedaan mendasar antara teori koherensi dengan teori korespondensi ialah
kebenaran teori korespondensi ditentukan oleh objek dari pernyataan tersebut.
Sedangkan kebenaran teori koherensi ditentukan oleh subjek. Jika untuk
membuktikan kebenaran menurut teori korespondensi harus langsung melihat objek
dari proposisi tersebut, jika tidak ditemukan objek itu maka proposisi itu salah. Teori
koherensi tidak memerlukan itu, bagi teori korespondensi, kebenaran cukup hanya
dengan menggunakan logika.
3. Teori Kebenaran Pragmatis
Teori kebenaran pragmatis merupakan teori baru yang lahir di Amerika pada
abad ke-20 M. Pencetus pertamanya ialah Charles S. Pierce (1839-1914 M). Teori
tersebut kemudian dikembangkan oleh William James (1842-1910 M) dan John
Dewey (1859-1952 M).68
Teori kebenaran pragmatis mencurahkan perhatian pada
dampak dari suatu pengetahuan, teori atau pernyataan. Ia menawarkan kebenaran
praktis di mana manfaat secara praktis menjadi tolok ukur kebenaran. Kebenaran
pragmatis justru terfokus pada manfaat atau dampak terhadap kehidupan.69
Teori
kebenaran pragmatis adalah teori mengajarkan bahwa pernyataan atau pengetahuan
yang benar adalah pernyataan yang dapat membuktikan dirinya sebagai benar
dengan perantara akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis.70
Selama suatu
pernyataan itu bermanfaat bagi manusia, selama itu juga pernyataan itu akan dinilai
sebagai kebenaran.
Charles S. Pierce71
justru memahami teori ini sebagai teori objektif dan
impersonal, karena memang teori ini tidak didasarkan hanya semata-mata atas
pandangan ilmuwan atau kelompok yang otoritatif, tetapi berdasarkan pengamatan
terhadap praktek-praktek yang diteliti secara ketat. Ketika praktek-praktek tersebut
memang merespons dan berdampak sesuai dengan kehidupan nyata pada
masyarakat, maka di situlah sebenarnya letak kebenaran objektif. Di mana keadaan
suatu teori ditentukan oleh realitas yang berkaitan dengan banyak masyarakat, bukan
hanya ditentukan oleh individu-individu seperti para ilmuwan.72
Ketika teori para
68
Fauziah Nurdin, “Kebenaran Menurut Pragmatisme dan Tanggapannya Terhadap
Islam”, dalam Islam Futura 13. No. 2, Februari 2014, h. 186. 69
Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2, (Yogyakarta: Kanisius,1989),
130-132. 70
Beniharmoni Herafa, “Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum”, dalam
Komunikasi Hukum 2, no. 1, Februari 2016, h. 17. 71
Charles S. Peirce merupakan bagian dari tokoh pendiri pragmatisme yang berasal
dari Amerika. Pragmatisme berasal dari bahasa inggris yaitu pragmatic yang berarti
berkaitan dengan hal yang bersifat praktis. A. Mangun Harjana, Isme-isme dalam Etika dari
A Sampai Z, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 189. 72
R Ormerod, “The History and Ideas of Pragmatism”, dalam The Operational
Research Society 57, no. 8, 2006, h. 892.
35
ilmuwan menjadi dogma yang dapat menentukan benar salah, maka sesungguhnya
apa yang ia katakan hanyalah berdasarkan praktek ilmiahnya yang bersifat individu.
Apa yang secara individu dilakukan oleh para ilmuwan tidak akan sampai pada
kebenaran. Terbukti selama ribuan tahun para ilmuwan terus menerus mengubah
pernyataan mereka, tampaknya pada pandangan ini kebenaran juga berubah. Teori
kebenaran pragmatis ini sebenarnya suatu teori yang sangat realistis. Bahkan Pierce
mengatakan bahwa kebenaran ilmu hanya dapat dipahami melalui interaksi sosial,
karena itu merupakan keprihatinan komunitas.73
Tolok ukurnya berdasarkan kondisi-
kondisi yang langsung menyentuh pada kehidupan masyarakat, tidak seperti teori
lainnya yang spekulatif dan mengesampingkan kehidupan manusia.
Teori kebenaran pragmatis oleh Peirce ini dilatarbelakangi oleh pribadinya.
Ia pada dasarnya bukan hanya sosok filosof, lebih dari itu ia juga seorang saintis
khususnya di bidang fisika yang banyak berkecimpung di laboratorium. Di samping
itu, itu adalah seorang yang mempunyai keyakinan moral yang begitu kuat.74
Maka
tidak heran ketika ia kemudian mempunyai pemikiran yang fokus pada manfaat.
Dalam pandangannya tentang teori kebenaran ia mengatakan bahwa teori/pernyataan
dapat dikatakan sebagai benar apabila teori tersebut mempunyai manfaat. Maka
untuk mengukur kebenaran suatu pernyataan ialah dengan cara melihat fungsinya
dalam kehidupan praktis. Penyataan atau pengetahuan dapat dikatakan benar apabila
ia dipercaya dapat memberikan kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari.75
Seperti yang dikatakan Bacon bahwa pengetahuan menjadi tidak berarti ketika ia
tidak mampu mengubah manusia kepada kehidupan yang lebih baik.76
Teori kebenaran pragmatisme Pierce ini jika dikaitkan dengan keyakinan
tampaknya menarik. Suatu keyakinan atau kepercayaan dapat dikatakan benar
selama ia dapat membawa hasil terbaik bagi kehidupan seseorang seperti dapat
meningkatkan kesuksesan dan lainnya. Namun apabila keyakinan itu justru
sebaliknya maka keyakinan itu adalah salah. Dari yang telah dipaparkan di atas
tampaknya dapat kita pahami bahwa teori kebenaran pragmatisme yang ditawarkan
oleh Charle S. Pierce ini bersifat relatif. Suatu pernyataan yang sama akan menjadi
benar dan salah dalam situasi dan kondisi berbeda yang membuat fungsi atau
manfaat dari suatu pernyataan atau teori itu juga berubah. Kebenaran menurut
perspektif teori pragmatis ialah tidaklah tetap, kebenaran akan terus berubah-ubah
sesuai dengan perubahan fungsi dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
Selama dampak tidak berubah, selama itu pula kebenaran atau kekeliruan tidak akan
berubah.77
Seorang filosof kelahiran New York, William James menguatkan penjelasan
tentang teori kebenaran pragmatis dengan mengatakan “that it is useful because it is
73
Rodliyah Khuza‟i, Dialog Epistemologi Mohammad Iqbal Dan Charles S. Peirce
..., h. 88. 74
Titus, dkk, Persoalan-persoalan Filsafat, Penerjemah H.M. Rasjidi, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1984), h. 341. 75
Fauziah Nurdin, “Kebenaran Menurut Pragmatisme dan Tanggapannya Terhadap
Islam”, dalam Islam Futura 13, no. 2, Februari 2014, h. 192. 76
Nunu Burhanuddin, “Pemikiran Epistemologi Barat: dari Plato Sampai Gonseth”,
dalam Intizar 21, no. 1, Januari 2015, h. 137. 77
Fauziah Nurdin, Kebenaran Menurut Pragmatisme ..., h. 186.
36
true' or that 'it is true because it is useful.” (bahwa itu berguna karena itu benar atau
bahwa itu benar karena itu berguna.)78
Tanpa ada kegunaan maka pengetahuan tidak
akan mungkin dikatakan benar, karena kebenaran akan selalu manfaat yang baik
buat manusia. Kebenaran dalam pandangan teori ini adalah nyata dan merasuk ke
dalam kehidupan manusia. Struktur realitas tidak mempunyai nilai nyata pada
kehidupan, karena ia tidak tampak, sehingga ia tidak dapat menentukan kebenaran.
Justru kondisi yang memiliki nilai nyata adalah pengetahuan yang sesuai dengan
kondisi di mana kita menerima kalimat tersebut sebagai benar. Apa yang ingin kita
ketahui adalah seberapa dapat diterima penerimaan kita. Biasanya teori semacam ini
berkaitan untuk mengungkap praktek sosial yang ada di balik penilaian kita tentang
apa yang diterima. Jadi kita menyebut teori semacam itu sebagai teori kebenaran
"pragmatis".
Teori kebenaran pragmatis ini menekankan pada konsekuensi praktis. Oleh
karenanya kebenaran yang sudah dibuktikan melalui teori korespondensi maupun
koherensi tidak dapat diterimakan manakala dalam prakteknya tidak dapat
diterapkan atau justru memberikan malapetaka bagi kehidupan. Teori, bagi teori
kebenaran ini, tidak lebih penting daripada manfaat dalam praktek.79
Karena dunia
praktek lebih real daripada teori. Justru yang dibutuhkan manusia sesungguhnya
manfaat atau dampak baik terhadap kehidupan. Fungsi praktis justru menjadi tujuan
dalam setiap teori, karena teori dibuat hanya untuk melahirkan kebaikan-kebaikan
praktis bagi umat manusia. Suatu teori atau pengetahuan dikatakan benar karena ia
bermanfaat, jadi pengetahuan itu bermanfaat karena ia adalah benar.80
Jenis lain dari teori pragmatis menganggap kebenaran sebagai semacam
keadaan yang berharga. Dengan demikian, menerima hal-hal tertentu mungkin
sangat berharga bagi kelangsungan hidup kita sehingga kita menganggap apa yang
kita terima adalah benar. Tetapi seperti yang dicatat oleh berbagai filsuf, tidak ada
alasan bahwa apa yang berharga bagi kelangsungan hidup kita perlu ada
hubungannya dengan cara dunia ini, yang akan menjadi kegagalan teori. Tentu saja,
pragmatis dapat menjawab bahwa tidak masuk akal untuk berbicara tentang cara
dunia terlepas dari praktek kita.
C. Pandangan Islam tentang Kebenaran
1. Kebenaran menurut Al-Ghazālī
Nama lengkap al-Ghazālī (1058-1111 M) ialah Abû Ḥâmid Muḥammad ibn
Muḥammad al-Ghazālī. Dalam kaitannya dengan kebenaran ia mengatakan bahwa
indra tampaknya bisa saja mencapai kebenaran sesuai dengan jangkauannya. Indra
hanya mampu menangkap kebenaran-kebenaran yang bersifat lahir seperti apa yang
terdapat pada alam. Setiap indra masing-masing mempunyai daya tangkap terhadap
kebenaran yang berbeda.81
Indra perasa bagi manusia berfungsi sebagai suatu alat
78
William James, “Pragmatism: A New Name For Some Old Ways Of Thinking”,
February 2013. Artikel diakses pada 15 Agustus 2019 dari
https://www.gutenberg.org/files/5116/5116-h/5116-h.htm#link2H_4_0008 79
R Ormerod, “The History and Ideas of Pragmatism”, dalam The Operational
Research Society 57, no. 8, 2006, h. 894. 80
R Ormerod, “The History and Ideas of Pragmatism ..., h. 894. 81
Ahmad Zainul Hamdi, Tujuh Filsuf Muslim ..., h. 157-158.
37
yang dapat menangkap kebenaran dari suatu rasa seperti panas, dingin, kasar, lunak,
kering, basah dan sebagainya, namun alat ini tidak dapat menjangkau alam warna.
Warna merupakan daerah jangkauan alat penglihatan (mata). Bagi mata, kering,
lunak dan lainnya seakan tidak ada, padahal ada hanya saja mata tidak dapat
menangkapnya. Maka sebenarnya kebenaran empiris ini dapat dijangkau indra
sesuai porsinya masing-masing.
Dari konsep ini tampaklah bahwa ia tidak menolak kebenaran empiris.
Pengakuannya terhadap kebenaran empiris ditandai oleh pengakuannya terhadap
realitas materi. Al-Ghazālī membagi realitas menjadi realitas materi yang ia sebut
dengan „ālam al-syahādah dan realitas immateri yang ia namai dengan ‘ālam al-
malakūt atau ‘ālam al-ghaib.82
Alam materi adalah alam yang tampak pada mata dan
indra. Maka kebenaran ini, harus diverifikasi berdasarkan pancaindra. Namun, ia
kemudian meletakkan kebenaran materi sebagai kebenaran yang berada pada level
kebenaran rendah. Meskipun demikian, ia tetap menerima kebenaran materi sesuai
porsi indra.83
Ia mengatakan demikian karena alat yang digunakan sebagai
penangkap kebenaran materi (indra) mempunyai berbagai kekurangan yang
memungkinkannya sering keliru dalam mengungkap suatu fakta. Tongkat yang
dicelupkan ke dalam air menampakkan diri kepada mata sebagai tongkat yang
bengkok. Pada kasus ini indra menangkap realitas yang keliru, karena pada dasarnya
tongkat tersebut adalah lurus.
Di samping kebenaran materi, ia juga mengatakan bahwa terdapat
kebenaran logis yang ditangkap oleh akal. Akal mampu menangkap yang tidak
ditangkap oleh indra. Kebenaran level ini dinilai olehnya sebagai kebenaran lebih
tinggi dari kebenaran materi. Akal oleh al-Ghazālī disebut sebagai cahaya di atas
cahaya. Ia mengatakan bahwa akal tidak akan bertentangan dengan syara‟. Maka
dari itu akal tidak mungkin menetapkan sesuatu yang tidak dapat diterima
kebenarannya oleh syara‟. Demikian pula dengan syara‟, ia tidak mungkin
menetapkan suatu kebenaran yang tidak dapat dibuktikan oleh akal. Syarat akal
mampu menangkap kebenaran ialah cemerlang, kritis dan mandiri bukan akal yang
taklid kepada pendapat seorang pemikir besar muslim, tanpa mengkajinya terlebih
dahulu.84
Maka jika syarat ini tercapai maka kebenaran yang diperoleh melalui akal
tidak akan bertentangan dengan iman. Ia kemudian menyerukan untuk mencari
kebenaran dengan cara berpikir dengan nalar yang bebas. Meskipun demikian,
keinginan al-Ghazālī adalah mencari kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran yang
tidak diragukan lagi termasuk mencari melalui akal, seperti sepuluh lebih banyak
daripada tiga. Namun al-Ghazālī ragu. Sekiranya ada orang yang mengatakan bahwa
tiga lebih banyak daripada sepuluh dengan mengatakan bahwa tongkat bisa berubah
menjadi ular, dan hal itu memang terjadi, al-Ghazālī merasa kagum akan realitas
82
A. Khudori Soleh, Wacana Baru Filsafat Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004), h. 84-85. 83
A. Khudori Soleh, Wacana Baru Filsafat Islam ..., h. 85. 84
Yusuf Qardhawi, al-Ghazālī antara Pro dan Kontra. Penerjemah Hasan Abrori,
(Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), h. 25.
38
tersebut, tetapi sungguhpun demikian keyakinannya bahwa sepuluh lebih banyak
dari tiga tidak akan goyang. Kebenaran seperti inilah yang ingin dicari al-Ghazālī.85
Akal dapat menunjukkan kebenaran seorang Nabi. Namun sebenarnya akal
mempunyai batasan-batasan tersendiri. Akal mempunyai rel-rel yang tidak dapat ia
lampaui begitu saja. Batasan-batasan akal di antaranya ialah pada permasalahan
mengenai Allah dan hari akhir. Maka mengenai hal yang berkaitan dengan Allah,
seperti mu‟jizat Allah, akal tidak dapat menentangnya. Peran akal dalam hal tersebut
adalah membenarkan atau menetapkan apa yang telah Allah mu‟jizatkan. Alasan
akal harus menerima wahyu adalah wahyu bersifat maʻsūm atau terpelihara
kebenarannya, sedangkan akal tidak. Maka sesungguhnya akal tidak dapat
menjangkau fenomena batin. Akal hanya mampu memikirkan sesuatu yang nyata
berdasarkan pengertian-pengertian dasar (awwalī), Kant menyebutnya dengan istilah
kategori.86
Tidak mampunya dalam menangkap kebenaran yang bersifat batin seperti
ketidakmampuan pendengaran dalam mengenali warna-warna, tidak mampunya
penglihatan mengenali suara atau tidak mampunya seluruh pancaindra di dalam
mengenali hal-hal yang rasional (maʻqūlāt). Jadi fenomena batin adalah ranah yang
bukan lagi area akal, akan tetapi sudah area hati, maka dari itu akal tidak bisa
mencapainya.87
Bagi al-Ghazālī intuisi menempati posisi di atas akal. Intuisi dapat
menangkap wahyu yang kebenarannya lebih pasti dibandingkan akal. Sedangkan
akal tidak dapat menangkapnya, karena akal terlalu lemah untuk menangkap realitas
wahyu.88
Akal hanya dapat mengiakan segala yang datang dari wahyu. Alasan inilah
yang kemudian menjadikannya memilih untuk menjadi sufi dibandingkan menjadi
filosof. Pada kondisi ini yaitu dalam rangka mencapai kebenaran intuitif, al-Ghazālī
menegaskan bahwa kebenaran batin hanya bisa dicapai melalui dhauq89
. Dhauq
merupakan kekuatan batin yang dengannya ia mendapatkan pengalaman secara
langsung yang berada di luar jangkauan akal.90
Maka pengetahuan yang benar menurutnya merupakan hasil dari pencerahan
Ilahi.91
Ketika Tuhan menjaga hati, dada tercerahkan dan misteri alam spiritual
tersingkap, dan tabir kesalahan sirna dan realitas hal-hal yang ilahi bersinar dalam
hati. Sekali hati menjadi pemilik kebenaran, pikiran pun memperoleh kepastian.
Sebagaimana dikatakan al-Ghazālī:
ا العقلي را عقبار ةا بوبوةها بها قلا ميا وعلينا ا الر ر ورويهار لر ت ا,اور ر اداللن ارماوكرياذاكا نظمر
ورا,ا و وليرا كالنا . لا نبواوقذفرا راولقلاذفا الصت92ا
85
Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 28. 86
Ahmad Zainul Hamdi, Tujuh Filsuf Muslim ..., h. 155-156. 87
Yusuf Qardhawi, al-Ghazālī antara Pro dan Kontra ..., h. 27. 88
Seyyed Hossein Nasr, Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam. Penerjemah Tim
Penerjemah Mizan, (Bandung: Mizan, 2003), h. 321. 89
Henri Bergson menyebut istilah zhauq (mata hati) dengan kata intuisi. Ahmad
Zainul Hamdi, Tujuh Filsuf Muslim ..., h. 161. 90
Ahmad Zainul Hamdi, Tujuh Filsuf Muslim ..., h. 157. 91
Seyyed Hossein Nasr, Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam ..., h. 320. 92
al-Ghazālī, al-Munqidh min al-Ḍalāl, (Bairūt: Dāru al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 1988),
h. 29.
39
“Kebenaran-kebenaran rasional diperoleh kembali karena saya
memperoleh kembali keyakinan terhadap kepastian dan
kepatutannya untuk dipercaya. Ini tidak diperoleh melalui
demonstrasi yang sistematis atau argumen yang tertata, tetapi
melalui cahaya yang diberikan oleh Allah yang maha tinggi ke
dalam dada.”
Dalam kutipan tersebut tampak bahwa ia ingin mengatakan bahwa cahaya
yang Allah tuangkan dalam dada seseorang akan menyingkap tirai batin. Ketika tirai
batin sudah tersingkap, maka tampaklah segala berbagai kepastian-kepastian.
Maka, tidak heran ketika pada akhir hayatnya ia berlabuh pada keyakinan
terhadap tasawuf dengan berkata “saya memahami sejelas-jelasnya bahwa para sufi
adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman yang benar... apa yang masih ada
pada saya tidak akan tercapai melalui ajaran-ajaran lisan dan studi, tetapi hanya
melalui pengalaman langsung dan menapaki jalan sufi.”93
Keadaan ini dapat
menyingkap objek pengetahuan sehingga tidak lagi menyisakan keraguan, tidak lagi
mengusung kemungkinan kesalahan, dan tidak memberikan ruang dalam jiwa untuk
mengetahui berdasarkan perkiraan.94
Pencapaian kondisi ini akan meniscayakan
seorang sufi memperoleh pencerahan jiwa atau batin dan pada gilirannya akan
mampu menangkap pengetahuan dan kebenaran lewat pengalaman intuitif.95
Kebenaran ini olehnya dianggap sebagai kebenaran objektif. Pemikiran ini
yang kemudian oleh Khodari disebut sebagai pemikirannya berbeda dengan
Aristoteles maupun Platonik.96
Baginya kebenaran bukan terletak pada seseorang
yang mengatakannya melainkan kebenaran terletak pada diri kebenaran itu sendiri.
Kepada Kamil bin Ziad ia mengatakan “jangan engkau pandang kebenaran itu
karena orang yang mengatakannya, akan tetapi pandanglah kebenaran itu karena
suatu kebenaran (siapa pun yang mengatakannya). Selama seseorang mengatakan
bahwa suatu kebenaran itu –apabila terjadi pertentangan dengan pendapat orang
yang kesohor sebelumnya- adalah dengan melihat siapa yang mengatakan, sudah
pasti dia akan jatuh pada kesesatan.”97
Dari apa yang disampaikan di atas, tampaklah sudah bahwa sesungguhnya
al-Ghazālī membagi kebenaran menjadi 3, yaitu kebenaran yang dapat dicapai
melalui indra, kebenaran yang dapat dicapai melalui akal dan kebenaran yang
diperoleh dari pengalaman batin. Kebenaran yang terakhir adalah kebenaran hakiki,
di mana yang ditangkap langsung oleh intuisi adalah objek hakiki berupa wujud
Tuhan. Kebenaran empiris merupakan kebenaran pada level paling rendah.
Sedangkan kebenaran akal adalah kebenaran yang berlevel di antara kebenaran
intuitif dan kebenaran empiris.
93
Seyyed Hossein Nasr, Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam ..., h. 328. 94
Al-Ghazālī, Tahāfut al-Falāsifah. Penerjemah Ahmad Maimun, (Yogyakarta:
Grup Relasi Inti Media, 2015), h. xxxii. 95
Amin Hasan, “Menyusuri Hakikat Kebenaran: Kajian Epistemologi atas Konsep
Intuisi dalam Tasawuf al-Ghazali”, dalam At-Ta’dib, vol. 7, no. 2, Desember 2012, h. 198-
199. 96
A. Khudori Soleh, Wacana Baru Filsafat Islam ..., h. 89. 97
Yusuf Qardhawi, al-Ghazālī antara Pro dan Kontra ..., h. 42.
40
2. Kebenaran menurut Ibnu Sīnā
Nama lengkap Ibnu Sīnā (980-1037 M) ialah Abû 'Alî al-Husayn bin
'Abdullâh bin Sīnā. Di Barat ia dipanggil dengan nama Avicenna.98
Meskipun ia
lahir di Uzbekistan, ia digolongkan sebagai salah satu filosof besar Islam Persia,
karena ia hidup dan mati di Persia (Iran). Sebagai salah satu Filosof Persia yang
berpikiran cemerlang, maka ia menjadi salah satu tokoh yang sangat dihormati oleh
Murtaḍá Muṭahharī.99
Sebagai salah satu filosof besar, Ibnu Sīnā telah merumuskan
bangunan tentang teori kebenaran yang sudah tercantum dalam karya-karyanya.
Dalam kajian filsafat, Ibnu Sīnā menyebut kebenaran dengan istilah hikmah.
Lebih lanjut Ibnu Sīnā mengatakan bahwa kebenaran merupakan adanya
keterhubungan antara ilmu, kenyataan dan perasaan. Istilah ilmu oleh Imron
Mustofa dibahasakan dengan istilah cara berpikir. Sedangkan kata lain dari
kenyataan adalah al-ḥaqīqah. Perasaan ia sebut dengan kata intuisi. Berdasarkan
yang dijelaskan tadi, tampaknya kebenaran kemudian dapat kita bagi tiga di
antaranya ialah pertama kebenaran bersifat intuitif atau kebenaran dari wahyu.
Kedua, kebenaran yang bersifat rasional atau kebenaran dari filsafat. Sedangkan
yang terakhir ialah kebenaran yang bersifat eksistensial atau kebenaran yang
eksistensinya dapat dibuktikan.100
Pertanyaan berikutnya yang muncul ialah bagaimana cara mengetahui
kebenaran. Bagi Ibnu Sīnā untuk mengetahui kebenaran ialah dengan cara
mengetahui eksistensi dari suatu hal. Eksistensi kebenaran menurutnya akan
memperjelas apa yang benar dan apa yang salah. Maka tidak heran ketika Seyyed
Husein Nasr menjelaskan bahwa eksistensi Ibnu Sīnā merupakan penentu dari segala
hakikat dan menentukan segala kualitas sesuatu yang ada. Sedangkan syarat untuk
mengetahui tentang eksistensi yang salah dan yang benar ialah pengetahuan yang
mempuni tentang hal tersebut. Maka dari itu dibutuhkan akal dan wahyu untuk
mencapai kebenaran. Akal bagi manusia biasa, sedangkan wahyu bagi manusia yang
diberi kesempatan langka oleh Allah untuk mendapat pengetahuan tanpa usaha dari
dia sendiri.101
Tanpa keduanya manusia tidak akan pernah sampai pada kebenaran.
Akal bagi Ibnu Sīnā mempunyai kemampuan untuk mengetahui kebenaran
yang hakiki. Jika akal berfungsi dengan baik dan benar, maka seseorang pasti akan
menemukan kebenaran. Kebenaran yang hakiki itu tidak akan pernah bertentangan
dengan wahyu.102
Tampaknya akal mempunyai posisi tinggi bagi Ibnu Sīnā
dibandingkan dengan lainnya seperti indra dan hati. Oleh karena itu seseorang yang
menggunakan akal seperti para filosof mempunyai posisi yang tinggi baginya
98
Syahruddin el-Fikri, “Sejak Kecil, Ibnu Sīnā Belajar Menghafal al-Quran”, artikel
diakses pada 28 Agustus 2019 dari https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-
digest/17/03/18/on01bn313-sejak-kecil-ibnu-sina-belajar-menghafal-alquran 99
Penghormatan tersebut terejawantahkan dalam kegigihan Murtaḍá dalam
mempelajari dan mendalami al-shifā‟ karya Ibnu Sīnā. Achmad Chumaedi, “Pemikiran
Murtaḍá Muṭahharī Tentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi
Islam Iran”, dalam Journal of Government and Civil Society, vol. 2, no. 1, April 2018, h. 36 100
Imron Mustofa, “Konsep Kebenaran Ibnu Sīnā”, dalam Kalimah, vol. 15, no. i,
Maret 2017, h. 4-5. 101
Seyyed Hossein Nasr, Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam ..., h. 290. 102
Imron Mustofa, “Konsep Kebenaran Ibnu Sīnā” ..., h. 5.
41
dibandingkan dengan manusia lainnya. Bahkan Ibnu Sīnā menganjurkan manusia
agar berfilsafat jika hendak mencapai kebenaran hakiki. Tanpa berfilsafat sulit
rasanya untuk mendapatkan kebenaran hakiki.
Penerapan kebenaran teori kebenaran ini tampak pada pembuktian Ibnu Sīnā
terhadap keberadaan jiwa. Ibnu Sīnā setuju jika jiwa merupakan wujud yang
keberadaannya tidak dapat diragukan lagi. Akan tetapi untuk membuktikannya
secara materi, yaitu wujud materi jiwa dipertanyakan maka Ibnu Sīnā dan lainnya
akan mengalami kesulitan bahkan tidak dapat membuktikannya. Namun Ibnu Sīnā
mencoba membuktikan keberadaan jiwa melalui pendekatan logika.
Menurutnya jiwa dapat dibuktikan dengan 4 argumen di antaranya ialah
dalil alam kejiwaan, dalil aku dan kesatuan gejala-gejala kejiwaan, dalil
kelangsungan dan dalil orang terbang dan orang tergantung di udara. Dalam
argumentasi yang berikan oleh Ibnu Sīnā, tidak ada menunjukkan adanya unsur
materi dari jiwa. Yang ada adalah argumen penguatan-penguatan yang rasional.
Selama suatu alasan itu telah memenuhi kaidah-kaidah logika yang tepat dan secara
logika berargumen kuat, maka selama itu pula suatu itu dapat dikatakan benar. Ibnu
Sīnā menerima kebenaran tentang jiwa melalui penjelasan rasional. Ibnu Sīnā ingin
menunjukkan bahwa jiwa mempunyai hakikatnya sendiri. Pembuktian keberadaan
jiwa olehnya dikatakan merupakan pembuktian secara langsung karena pikiran tidak
memerlukan perantara untuk mengenali dirinya sendiri. Maka ketika jiwa berpikir,
maka ketika itu juga jiwa ada, karena pemikirannya sama benar dengan wujudnya.103
Teori kebenaran ini tampaknya sama dengan yang dikatakan oleh Descartes
yang mengatakan “aku berpikir maka aku ada”. Namun apakah betul Descartes telah
mendapat pengaruh dari Ibnu Sīnā? Menurut Hanafi, tidak ada bukti-bukti yang
menjelaskan bahwa Descartes terpengaruh oleh pemikiran Ibnu Sīnā. Kemungkinan
yang terjadi ialah Descartes membaca teori jiwa Augustinus yang ketepatan teorinya
mempunyai kemiripan dengan Ibnu Sīnā. Namun Furlani sebenarnya masih
membuka kemungkinan hal tersebut terjadi, yaitu Descartes membaca karangan
Ibnu Sīnā melalui Guillaume Averni.104
3. Kebenaran menurut Syed Muḥammad Naqīb al-‘Aṭās
Naqīb al-„Aṭās (1931 M) adalah seorang filosof yang lahir di Bogor dan
berkiprah di Malaysia. Dalam menanggapi tentang kebenaran ia pun mengatakan
bahwa manusia pada dasarnya mampu mencapai kebenaran-kebenaran terutama
kebenaran tentang pengetahuan yang bersifat materi. Bahkan kebenaran yang
manusia capai hingga kini terus mengalami perkembangan yang begitu pesat. Akan
tetapi apakah kebenaran yang telah dicapai umat manusia kini itu merupakan
kebenaran hakiki? Menurut Naqīb al-„Aṭās, kebenaran yang dicapai manusia pada
dunia modern ini tampaknya bukanlah kebenaran hakiki, mengingat kebenaran
hakiki itu adalah kebenaran suatu pengetahuan yang mempunyai pengaruh langsung
terhadap individu manusia karena menyangkut identitas dan nasibnya. Salah satu
tandanya ialah terbebasnya seseorang dari ketundukan terhadap tuntutan fisik,
karena ia cenderung kepada sekularisme dan ketidakadilan yang berdampak pada
103
Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996), h.
130. 104
Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam ..., h. 31.
42
pengabaian terhadap kebenaran jiwa. Manusia secara fisik cenderung melupakan
alam sejatinya serta mengabaikan tujuan hakikinya.105
Maka Naqīb al-„Aṭās
memandang bahwa dunia modern ini mengalami krisis kebenaran yang begitu parah
karena kebenaran telah kehilangan esensinya. Maka kebenaran yang ditawarkan oleh
modernisme adalah kebenaran semu. Hal-hal yang menyebabkan itu terjadi adalah
terlalu menonjolnya kebenaran materi, mementingkan hal yang bersifat jasmani dan
kemudian meninggalkan bahkan menghancurkan rohani.
Lalu seperti apa kebenaran yang hakiki menurutnya? Baginya kebenaran
hakiki bukan hanya kesesuaian antara suatu teori dengan realitas atau fakta. Lebih
dari itu, kebenaran baginya adalah kebenaran yang juga diimbangi dengan manfaat
dari kebenaran suatu teori tersebut. Maka kebenaran hakiki adalah keserasian antara
pernyataan, fakta dengan penilaian. Ukuran manfaat tidaknya suatu
teori/ilmu/pernyataan adalah dapat dinilai dari 4 aspek106
yaitu 1) kebenaran tersebut
mampu semakin mendekatkan diri seseorang kepada Allah (sebagai penguat ia
mengutip hadis)107
, 2) dapat membatu manusia merealisasikan tujuannya (QS: al-
Taubah: 40)108
dapat menjadi pedoman bersama (mengutip hadis ) dan 4) dapat
menyelesaikan persoalan umat (QS Luqmān: 30).
Tampaknya pengutipan ayat dan hadis dalam membatasi istilah manfaat, ia
ingin menunjukkan bahwa dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa mengenai
batasan-batasan tersebut. Maka pembatas yang diambil dai al-Qur‟an dan hadis itu
merupakan penekanan bahwa batasan itu batasan dalam menentukan kebenaran
dalam Islam. Bahkan ia mengatakan bahwa wahyu mempunyai sisi kebenaran yang
mutlak.109
Secara ringkas ia menekankan bahwa pengetahuan yang benar menurut
al-„Aṭās adalah pengetahuan yang mempunyai makna koheren dengan unit-unit
makna dan konsep-konsep kunci lainnya yang terdapat dalam sistem konseptual al-
Qur‟an.110
Maka dari itu kebenaran menurut Islam akan dikatakan benar apabila ia
mengandung manfaat dalam arti luas sebagai mana dijelaskan tadi.
Fakta bagi al-„Aṭās sepertinya tidak menjadi satu-satunya landasan dalam
menentukan kebenaran. Fakta tidak dapat menjadi satu-satunya landasan kebenaran
hakiki karena menurut al-„Aṭās fakta dapat juga dibuat oleh manusia sehingga fakta
bisa saja berada pada tempat yang tidak benar. Maka kebenaran harus meliputi
105
Wan Mohd Nor Wan Daud, Islamisasi Ilmu-Ilmu Kontemporer Dan Peran
Universitas Islam Dalam Konteks Dewesternisasi Dan Dekolonisasi, (Bogor: Universitas
Ibnu Khaldun Bogor, 2013), h. 18. 106
Achmad Charris Zubair, Filsafat Ilmu Menurut Konsep Islam, dalam Jurnal
Filsafat, Maret 1997, h. 39. 107
Nabi Saw bersabda: Sesungguhnya Allah ditaati dan. disembah dengan ilmu.
Begitu juga kebaikan dunia dan akhirat bersama ilmu, sebagaimana kejahatan dunia dan
akhirat karena kebodohan. 108
Dan kalimat Allah Itulah yang tinggi. (Q.S at-Taubah: 40). Kemudian ia
menambahkan dengan hadis Nabi saw bersabda: Barang siapa mati ketika sedang mencari
ilmu untuk menghidupkan Islam maka di surga ia sederajat di bawah para nabi. 109
Salafudin, “Islamisasi Ilmu Pengetahuan”, dalam Forum Tarbiyah 11, no. 2,
Desember 2013, h. 207. 110
Muḥammad Naqīb Al-„Aṭās, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M.
Naqīb al-‘Aṭās. Penerjemah Hamid Fahmy dkk, (Bandung: Mizan, 2003), h. 150.
43
wilayah jasmani dan rohani sekaligus. Suatu pernyataan bisa saja benar menurut
fakta akan tetapi bisa menjadi salah ketika pernyataan itu didasarkan pada penafsiran
yang salah terhadap manusia seperti rekayasa genetika. Meskipun teori rekayasa
genetika dari sudut pandang ilmu pengetahuan benar, premis-premisnya memenuhi
standar ilmu pengetahuan karena telah menggambarkan realitas yang benar, namun
menurut Naqīb ia tetap saja salah karena teori rekayasa genetika itu telah keliru
dalam menafsirkan hakikat manusia. Kekeliruan dalam menafsirkan hakikat
manusia disebabkan oleh penggunaan akal yang tidak sehat. Maka kemudian al-
„Aṭās menjadikan akal sehat sebagai salah satu syarat mencapai kebenaran. Akal
sehat menjadi penting bukan karena pikiran manusia sering keliru, tetapi pikiran
manusia kerap sekali dipengaruhi oleh estimasi dan imajinasi.111
Teori kebenaran al-„Aṭās merupakan suatu kritik terhadap teori kebenaran
Barat yang cenderung materialistik dan bahkan menafikan sisi metafisika.
Materialisme Barat yang mengajarkan pengetahuan yang sangat materialistik
mengakibatkan tidak mengakui kebenaran di luar itu. Bahwa tidak ada entitas-
entitas nonmateri seperti Tuhan.112
Keadaan ini seakan membuat pilihan kepada
kaum beragama agar memilih keyakinannya atau ilmu pengetahuan agama yang
banyak menyumbangkan pengetahuan bagi umat manusia. Padahal Islam juga
mengajarkan ilmu pengetahuan yang bersifat materi, rasional tanpa harus
meninggalkan pengetahuan jasmani. Maka Islam mengakui terdapat kebenaran
materi selain juga mengakui kebenaran rohani. Maka Islam sesungguhnya
menawarkan keseimbangan antara rohani dan jasmani, karena keduanya merupakan
saling melengkapi. Islam memberikan perhatian penuh kepada manusia dari aspek
lahir maupun batin.
Jika memang demikian, perbedaan mendasar dari peletakan teori kebenaran
antara Barat dan Islam adalah berada pada pemahaman Islam dan Barat terhadap
realitas. Islam mengakui terdapat realitas di luar materi yang biasa kita sebut dengan
realitas metafisik, sedangkan ilmuwan Barat modern terutama materialisme hanya
mengakui realitas materi. Maka dari itu fakta atau realitas di luar materi seperti
sesuatu yang metafisika tidak pernah dianggap materialisme. Karena tidak ada
realitas metafisik maka kebenaran metafisika pun dianggap tidak nyata dan salah.
Hal ini akan berdampak besar, teori kebenaran materialisme kemudian
berkesimpulan bahwa Tuhan, sebagai sesuatu yang bersifat immateri, merupakan
suatu dhāt yang keberadaannya tidak dapat dibenarkan. Berbeda dengan konsep
Islam yang dikatakan oleh al-„Aṭās, justru bagi kebenaran akan keberadaan Tuhan
menjadi tujuan akhir dari kebenaran yang hakiki. Ini lah sesungguhnya yang
membedakan konsep kebenaran Islam dan konsep kebenaran Barat.
Di kesempatan lain al-„Aṭās mengatakan bahwa seseorang akan sampai pada
kebenaran yang sesungguhnya ketika dalam diri seseorang terus terjadi ketiadaan
karakteristik madhmūmah (tercela) dan menguatnya karakteristik maḥmūdah
(terpuji). Ketika karakteristik sebagaimana dijelaskan tadi tercapai maka dengan
sendirinya semua informasi yang tidak benar dan salah akan hilang. Hal itu
disebabkan karena dalam unifikasi dengan al-ḥaq, dengan sendirinya semua yang
111
Muḥammad Naqīb Al-„Aṭās, Filsafat dan Praktek Pendidikan ..., h. 159. 112
Lorens Bagus, Kamus Filsafat ..., h. 594.
44
tidak sesuai dengan kebenaran akan hilang. Dengan penampakan kebenaran,
seseorang akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, sehingga yang
salah dapat diabaikan dan yang benar dapat disimpan. Dengan demikian yang tersisa
hanyalah informasi yang benar dan telah dibenarkan oleh kebenaran, sehingga
seseorang yang sampai pada keyakinan yang dilandasi oleh pengalaman langsung
(ḥaq al-yaqīn).
Keadaan ini hanya dicapai ketika seseorang sampai pada tingkat fanā’ al-
fanā’. Tingkat al- fanā’ ini keadaan seseorang dalam kondisi mukāshafah. Dalam
kondisi ini seorang hamba sesungguhnya sudah „mati‟, namun dihidupkan kembali
dalam keadaan dan tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi dengan kehidupannya di
sisi Tuhan. Ini lah yang disebut kebenaran yang didapatkan dari pengalaman
langsung (ḥaq al-yaqīn), yaitu suatu kebenaran yang kebenarannya sudah tidak
dapat diragukan lagi.
Ketika jiwa sampai, semua informasi yang salah akan hilang, sedangkan
yang tersisa hanyalah sesuatu yang dilandaskan oleh kebenaran mutlak sebagai
substratmu/dasar dari segala yang wujud. Pemahaman ini adalah ilmu yang tidak
bisa salah karena ia dilandaskan oleh ḥaq al-yaqīn sehingga akan memahami makna
dan arti setiap wujud dalam jiwanya. Keadaan ini akan menyingkap pengetahuan
hakiki yang rahasia dan ilmu di balik ciptaan Allah. Ini menurut al-„Aṭās bukan lah
kebenaran pengetahuan ilusi, tapi mempunyai realitas ontologis. Di sini lah
seseorang akan mencapai hakikat alam semesta dalam tingkat kebenaran tertinggi
sesuai dengan pemahaman metafisika waḥdatul al-wujūd yang berdasarkan al-
Qur‟an, sunnah dan para imam serta awliyā’ yang telah terlihat dengan akal dan
mencicipi dengan dhauqnya tentang pengalaman mukāshafah.
4. Kebenaran menurut Muḥammad Taqī Miṣbāḥ Yazdī
Miṣbāḥ Yazdī (1914 M) merupakan filosof kontemporer yang merupakan
murid dari Ṭabáṭabáī. Dalam hal kebenaran, Muhsin Labib mengatakan bahwa
kebenaran bagi Yazdī adalah persepsi yang sesuai dan sepenuhnya menyingkap
realitas sesuatu, sedangkan kekeliruan adalah anggapan (atau kepercayaan) yang
tidak sejalan dengan realitas.113
Yazdī kemudian mengatakan bahwa terdapat
pengetahuan yang memerlukan pembuktian mengenai keberadaan realitas dari
pengetahuan tersebut. Pengetahuan yang perlu pembuktian seperti itu disebut
pengetahuan dengan perantara. Subjek dan objek pada pengetahuan ini adalah
terpisah. Objek atau realitas berada di luar subjek. Sehingga pembuktian
kebenarannya harus disesuaikan dengan realitas yang terdapat di luar subjek. Jadi
realitas pada level ini dapat dikatakan tersingkap manakala pernyataan sesuai
dengan realitas objek.
Ada pula pengetahuan tanpa perantara yang kemudian ia sebut sebagai
pengetahuan ḥuḍūri. Pengetahuan merupakan pengetahuan di mana suatu objek
hadir langsung dan menyatu dengan subjek dalam persepsi seseorang melalui
pengalaman mental.114
Penjelasan ini dilontarkan oleh Muhsin ketika menjelaskan
113
Muhsin Labib, Pemikiran Filsafat M.T Miṣbāḥ Yazdī, (Jakarta: Sadra Press,
2011), h. 160. 114
M.T Miṣbāḥ Yazdī, Iman Semesta. Penerjemah Ahmad Marzuki Amin, (Jakarta:
al-Huda, 2005), h. 23.
45
tentang ilmu ḥuḍūri Miṣbāḥ Yazdī. Menurut Miṣbāḥ kekeliruan persepsi mudah
dibayangkan apabila terdapat penyulih antara pelaku persepsi dan entitas yang
dipersepsi. Dalam kasus pengetahuan perolehan inilah bisa timbul pertanyaan
apakah bentuk dan konsep yang menegahi antara subjek dan objek telah benar-benar
menyanterkan objek secara tepat dan sempurna atau tidak. Sebelum bentuk dan
konsep terbukti benar-benar sesuai dengan objek yang dipersepsikan, kepastian akan
kesahihan persepsi tidak akan pernah didapatkan. Akan tetapi, dalam hal objek atau
suatu yang dipersepsikan hadir tanpa perantara atau bahkan menunggal dengan
eksistensi pelaku persepsi, kekeliruan tidaklah dapat dibayangkan. Tidak mungkin
timbul pertanyaan ihwal apakah pengetahuan subjek telah sesuai dengan objek yang
diketahui, mengingat dalam kasus ini subjek pengetahuan identik dengan objek yang
diketahui.115
Aktivitas dan proses mental yang berlangsung kilat itu berbeda dengan
hadirnya ketakutan sebagai pengetahuan presentasional. Tetapi keseiringan dan
keserentakannya dengan pengetahuan presentasional sering menjebak orang dalam
kerancuan. Orang kerap menyangka bahwa karena ia menemukan keadaan takut
dalam dirinya melalui pengetahuan dengan kehadiran, ia pun mengetahui sebab
ketakutan tersebut melalui pengetahuan dengan kehadiran. Padahal, apa yang
dicerap melalui pengetahuan dengan kehadiran senantiasa bersifat sederhana, tanpa
bentuk dan konsep, dan bebas dari segala macam penafsiran dan penjabaran. Itulah
sebabnya mengapa pengetahuan dengan kehadiran tidak mungkin keliru.116
Sebaliknya, penafsiran seketika yang mengiringi hadirnya ketakutan dalam diri itu
merupakan persepsi-persepsi perolehan (dari informasi yang telah atau baru kita
terima dari luar diri kita) sehingga tidak menjamin kebenaran dan kesesuaiannya
dengan realitas yang sesungguhnya.
Teori kebenaran yang menjelaskan bahwa kebenaran merupakan kesesuaian
antara pernyataan dengan persepsi menurutnya tidak berlaku dalam teori kebenaran
huduri. Teori kebenaran korespondensi menurutnya hanya berlaku pada pernyataan
atau proposisi yang dapat dibandingkan dengan alam luar. Sedangkan proposisi-
proposisi metafisika tidak memiliki objek realitas eksternal yang bisa dijadikan
patokan kesesuaian. Dalam hal ini Yazdī tidak menolak korespondensi, karena
dalam tulisan Muhsin Labib dikatakan bahwa pengetahuan bagi Yazdī adalah
keyakinan yang selaras dengan realitas.117
D. Pandangan Barat tentang Kebenaran
1. Pandangan Kebenaran René Descartes (Rasionalisme)
Descartes (1596-1650 M) dijuluki sebagai bapak filsafat modern dan peletak
fondasi metode rasional untuk penelitian filosofis. Pemikirannya berkecenderungan
pada idealisme Platonian dan realisme Aristotelian. Namun, ia kemudian meyakini
bahwa pemikiran Platonian dan Aristotelian mempunyai kelemahan sehingga
melahirkan ketidakpastian. Di sinilah ia kemudian mencoba menemukan fondasi
kebenaran ilmu pengetahuan yang absolut dan pasti. Ketidakpastian pengetahuan
115
Muhsin Labib, Pemikiran Filsafat M.T Miṣbāḥ Yazdī ..., h.159-160. 116
Muhsin Labib, Pemikiran Filsafat M.T Miṣbāḥ Yazdī ..., h.159-160. 117
Muhsin Labib, Pemikiran Filsafat M.T Miṣbāḥ Yazdī ..., h.155.
46
melahirkan perdebatan. Sedangkan sumber perdebatan itu adalah adanya kebenaran
mutlak yang menjadi titik tolak yang tidak terbantahkan dalam menyusun ilmu
pengetahuan. Maka Descartes kemudian menjadikan akal sebagai dasar bagi ilmu
pengetahuan yang pasti serta mempertimbangkan segala hal di bawah pertimbangan
akal budi demi mendapatkan suatu kebenaran mutlak yang pasti.118
Baginya rasio merupakan sumber pengetahuan yang teramati dan terukur,
oleh karena itu rasio mampu menemukan kebenaran hakiki. Ketika garam
dicelupkan ke dalam air, garam tidak tampak kepada mata. Bagi mata garam tidak
ada. Namun rasio mampu mengetahuinya bahwa garam ada dan menyatu dengan air.
Pada contoh ini ditunjukkan bahwa sesungguhnya rasio lebih mampu menemukan
kebenaran daripada pengalaman indra. Rasio mampu menangkap hakikat, walaupun
wujud lahirnya telah berubah. Dalam hal ini, kebenaran justru terletak bukan pada
yang tampak, tetapi pada sesuatu yang tidak tampak dan itu hanya ditangkap oleh
rasio. Karena berbagai kasus kekeliruan yang dihasilkan oleh pengalaman indra,
maka pengetahuan yang dihasilkannya akan selalu menimbulkan keragu-raguan.
Sedangkan kebenaran adalah kepastian yang mutlak dan tidak berubah meskipun
dipengaruhi oleh ruang dan waktu.
Dalam rangka melahirkan kebenaran yang pasti, kokoh dan tidak
meragukan, Descartes menggunakan metode kesangsian. Suatu metode pencari
kebenaran dengan cara meragukan segala bentuk keyakinan yang ada.119
Descartes
mengatakan bahwa kita sering kali ditipu oleh pengalaman, bahkan meragukan
pemikiran rasional. Menurutnya bisa saja ada “setan jahat” yang menipu, yang bisa
memalsukan penalaran dan kebenaran secara sistematik, sehingga sesuatu yang
salah akan tampak sebagai kebenaran. Untuk membuktikan bahwa ia tidak tertipu,
maka Descartes bertolak dari adanya eksistensi Tuhan yang menjamin karena
menurutnya hanya Tuhan yang dapat menjamin bahwa ide-ide kita yang jelas dan
terpilah memang benar dan kita tidak ditipu oleh setan jahat.120
Begitu Descartes membuktikan adanya eksistensi Tuhan, maka ia merasa
memiliki dasar untuk mengakui: adanya tubuh kita yang berbeda dari rasio; bahwa
ide kita mengenai dunia luar adalah benar. Di sini tampak bahwa Aristoteles
mengandaikan bahwa adanya Tuhan menjadi ukuran segala pengetahuan, termasuk
menjamin aku yang menyangsikan dapat mencapai kebenaran.121
Setelah meragukan
segalanya bahkan dirinya sendiri, maka bagi Descartes ada sesuatu yang tidak dapat
diragukan keberadaannya, yakni bahwa saya sedang ragu. Adapun adanya saya ragu
itu secara langsung membuktikan adanya saya yang berpikir. “Aku berpikir”
merupakan kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi.122
Descartes ingin
mengatakan bahwa kebenaran sesungguhnya bukan berada di luar subjek, akan
tetapi berada dalam diri subjek sendiri.
118
Akhyar Yusuf Lubis, Filsafat Ilmu: Klasik Hingga Kontemporer, (Depok:
Rajawali Press, 2016), h. 94-96. 119
James Garvey, 20 Karya Filsafat Terbesar. Penerjemah C.P Mulyatno Pr,
(Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 56-67. 120
Akhyar Yusuf Lubis, Filsafat Ilmu ..., h. 100. 121
F. Budi Hardiman, Filsafat Modern: Dari Machiavaelli Sampai Nietzsche,
(Jakarta: Gramedia, 2007), h. 40. 122
Akhyar Yusuf Lubis, Filsafat Ilmu ..., h. 101.
47
Berdasarkan penjelasan di atas tampak bahwa “dapat diragukan” merupakan
salah satu cara dalam menentukan kepastian dan ketidakpastian segala sesuatu.
Usaha meragukan itu akan berhenti bila ada sesuatu yang tidak dapat diragukan lagi.
Usaha meragukan itu disebut metodik, karena keraguan yang diterapkan di sini,
merupakan cara yang digunakan oleh penalaran reflektif filosofis untuk mencapai
kebenaran. Bagi Descartes, kekeliruan tidak terletak pada kegagalan melihat sesuatu,
melainkan di dalam mengira tahu apa yang tidak diketahuinya, atau mengira tidak
tahu apa yang diketahuinya.123
Kebenaran baginya hanya didapatkan ketika ia
terbebas dari segala bentuk bayang-bayang keraguan. Dengan kata lain ia
mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat diterima dengan jelas melalui rasio
adalah benar.
Dalam pencarian kebenaran ini, Descartes mengibaratkan dirinya sebagai
orang yang berjalan sendirian dalam kegelapan. Ia tidak menggunakan apapun
sebagai pemandu, kecuali pikirannya sendiri. Dan karena ia tidak dibantu oleh
apapun, maka ia sudah siap kalau langkah pencariannya sedemikian lambat. Ia juga
sudah siap kalau hanya dapat menghasilkan sangat sedikit kemajuan, yang penting
adalah bahwa kemajuan itu akan sama sekali tanpa kekeliruan. Untuk itu, Descartes
menerapkan prinsip yang sangat ketat dalam pencariannya, yakni ia hanya akan
menerima pengetahuan yang jelas dan terpilah-pilah dan tidak mengizinkan sedikit
pun dugaan masuk ke dalam penalarannya. Menurutnya, ketidakpastian yang terjadi
dalam ilmu dan filsafat disebabkan karena para ilmuwan tidak puas dengan
pengetahuan yang jelas dan terpilah-pilah dan karena itu mencampur pengetahuan
itu dengan dugaan-dugaan spekulatif. Hasilnya adalah bahwa kesimpulan yang
ditarik dari cara demikian adalah kesimpulan yang didasarkan atas sejumlah
proposisi yang tidak jelas dan karena itu menjadi tidak pasti.124
Terdapat empat aturan yang dapat menjamin kepastian kebenaran yang
terangkum dalam prinsip metodologisnya. Di antaranya125
ialah Pertama, jangan
menerima apapun sebagai hal yang benar, kecuali jika kita mengenalnya secara jelas
dan terpilah berdasarkan rasio. Kita hanya menerima kebenaran yang pasti seperti
dalam matematika. Kedua, harus menganalisis sekecil mungkin, agar dapat
memecahkan masalah lebih mudah dan lebih baik. Ketiga, menata masalah dari
yang paling sederhana dan mudah dimengerti kemudian maju sedikit demi sedikit ke
tingkat yang lebih kompleks dan sulit. Keempat, merinci keseluruhan dan
mengevaluasi kembali secara umum sampai kita yakin bahwa kesimpulan yang kita
ambil tidak mengabaikan satu hal/masalah apapun. Selalu periksa kembali dengan
teliti apakah ada kesalahan ilmiah serta kesesuaian mendasar antara hukum alam
dengan hukum-hukum matematika.
123
Nunu Burhanuddin, “Pemikiran Epistemologi Barat: dari Plato Sampai
Gonseth”, dalam Jurnal Intizar 21, No. 1, 2015, h. 137. 124
Fitzerald Kennedy Sitorus, “RasionalismeRené Descartes: “Saya Berpikir, Maka
Saya Ada””, Makalah untuk Kelas Filsafat Filsafat Modern di Serambi Salihara, Sabtu, 12
November 2016. h. 7. 125
James Garvey, 20 Karya Filsafat Terbesar ..., h. 55.
48
2. Pandangan Bertrand Russel Empirisme tentang Kebenaran
Bertrand Russel (1872-1970 M) mengatakan bahwa fakta material sifatnya
mandiri dan tidak terpengaruh oleh ide. Ada tidak suatu ide, fakta materi tetaplah
ada. Sehingga jika ide dapat dikatakan benar, maka harus sesuai dengan fakta yang
ada.126
Dalam kaitannya dengan bahasa atau kalimat-kalimat, ia juga menekankan
bahwa kalimat atau bahasa yang benar adalah kalimat yang mendeskripsikan
kenyataan atau fakta.127
Kenyataan oleh Russel dijadikan sebagai syarat mutlak
suatu kebenaran dari proposisi.
Mengenai fakta Russell mengatakan bahwa fakta adalah segala sesuatu yang
di dunia. Matahari adalah fakta. Fattah makan nasi adalah fakta. Sakit gigi adalah
suatu fakta. Fakta adalah sesuatu yang ada apakah tiap orang berpikir tentang itu
atau pun tidak. Jika terdapat suatu pernyataan jika ia tidak dukung oleh adanya fakta
maka ia sebut pernyataan itu salah, jika didukung oleh fakta maka pernyataan itu
benar. Pernyataan Wafi pergi ke pasar. Jika memang faktanya Wafi pergi ke pasar,
maka pernyataan itu benar. Russell memandang bahwa fakta adalah faktor yang
menentukan suatu pernyataan benar. Fakta membuat suatu pernyataan menjadi benar
atau salah.128
Namun fakta tidak dapat dikatakan sebagai benar atau salah. Yang
dapat dikatakan benar dan salah adalah proposisi, karena fakta adalah
mengungkapkan fakta.129
Di sinilah ia mengatakan bahwa proposisi adalah sepadan
dengan dunia.
Dalam kaitannya dengan kepercayaan, Russel tampaknya mendefinisikan
kebenaran sebagai suatu hubungan tertentu antara kepercayaan dengan suatu fakta
atau lebih di luar kepercayaan. Jika tidak ada hubungan antara kepercayaan dengan
fakta di luarnya maka kepercayaan itu salah.130
Benar dan salah tampaknya tidak
tergantung kepada subjek tertentu, karena Russell mengatakan bahwa meskipun
tidak ada seorang pun yang mengakui suatu kebenaran, kebenaran akan tetap ada.131
Lebih lanjut kemudian ia memberikan contoh sebagai berikut. Seseorang sedang
tidur kemudian orang lain meneriakkan kebakaran. Seketika seseorang yang tidur
bangun dan langsung pergi keluar rumah. Kepergian dia keluar rumah adalah reaksi
atas kepercayaan dia atas terjadinya kebakaran. Ketika seseorang tersebut
memverifikasi kepercayaan itu dan memang terjadi kebakaran di rumah tersebut,
maka kepercayaannya benar dan sebaliknya. Namun ketika ia pergi begitu saja tanpa
memverifikasinya, maka kepercayaan itu akan tetap benar kalau memang benar-
benar terjadi kebakaran. Kepercayaan akan salah ketika tidak ada fakta tentang
kebakaran meskipun semua orang mengatakan ada kebakaran.
126
Nurani Soyomukti, Pengantar Filsafat Umum, h. 176. 127
Harry Hamersma, Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern, (Jakarta: Gramedia,
1992), h. 136. 128
Bertrand Russell, Fakta, Kepercayaan, Kebenaran dan Pengetahuan, dalam
buku Ilmu dalam Perspektif. Penerjemah Jujun S. Suriasumantri, (Jakarta: Yayasan Obor,
2009), h. 70-71. 129
K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer: Inggris-Jerman, (Jakarta: Gramedia,
2002), h. 29-30. 130
Bertrand Russell, Fakta, Kepercayaan, Kebenaran dan Pengetahuan ..., h. 76. 131
Bertrand Russell, Fakta, Kepercayaan, Kebenaran dan Pengetahuan ..., h. 77.
49
Richard L. Kirkham kemudian menjelaskan lebih detail bahwa keyakinan
adalah hubungan di antara empat hal yang berbeda. Pertama, adalah subjek, orang
yang memiliki keyakinan tersebut. Kedua, dan ketiga adalah dua istilah objek. Objek
pertama beranalogi dengan subjek kalimat; ia adalah perkara yang dianggap oleh
orang yang yakin sebagai melakukan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Objek
lainnya ialah analog dengan objek kalimat; ia adalah perkara yang dianggap terkena
sesuatu yang dilakukan atasnya. Keempat, adalah relasi objek yang secara mendasar
analog dengan kata kerja sebuah kalimat. Adalah relasi yang berdiri di antara dua
istilah objek. Jadi keyakinan Rahman bahwa “Andi mencintai Inayah” merupakan
relasi kompleks antara Rahman, si subjek; Andi, istilah Objek; Inayah; istilah objek
lainnya dan mencintai relasi objek.132
Menurut Richard suatu keyakinan bagi Russell dapat dikatakan benar ketika
sebuah keyakinan mempunyai satu kesatuan kompleks lainnya, di mana relasi salah
satu objek keyakinan mengandung objek lainnya. Jadi keyakinan benar ketika ia
berkorespondensi dengan sebuah kompleks berasosiasi tertentu dan salah ketika
tidak demikian. Kesatuan kompleks ini disebut dengan fakta yang berkorespondensi
dengan keyakinan. Jadi kebenaran sebenarnya mengandung kecocokan di antara dua
relasi yang kompleks. Pertama adalah hubungan empat-istilah keyakinan yang
berdiri antara Rahman, andi, Inayah dan mencintai. Yang kedua adalah hubungan
tiga-istilah yang disebut dengan “fakta” yang hanya mengandung andi, Inayah dan
mencintai. Jika terdapat hubungan tiga istilah semacam itu dan arahnya adalah sama
dengan hubungan empat-istilah dalam keyakinan Rahman, maka keyakinan itu
benar. Jika tidak terdapat hubungan tiga-istilah dengan istilah dan arah yang sama,
maka keyakinan itu salah. Dengan kata lain, jika di dunia ekstramental Andi benar-
benar mencitai Inayah, maka keyakinan Rahman bahwa Andi demikian adalah
benar.133
Untuk lebih jelasnya kami menyediakan diagram yang dapat dipelajari
dengan baik, yaitu:
Teori Russell tentang keyakinan yang benar
Barisan paling kiri pada diagram di atas menjelaskan bahwa keyakinan
Rahman tentang Andi mencintai Inayah berikut keempat istilahnya. Panah vertikal
132
Richard, Teori-Teori Kebenaran ..., h. 180-181. 133
Richard, Teori-Teori Kebenaran ..., h. 182.
50
melambangkan arahnya. Di sebelah kanan adalah fakta bahwa Andi mencintai
Inayah berikut ketiga istilahnya dan panah vertikal menunjukkan arahnya. (Tanda
sama dengan yang besar menunjukkan identitas) kedua hubungan itu (keyakinan dan
fakta) bisa dikatakan sejalan karena masing-masing dari kedua istilah objeknya,
Andi dan Rahman, muncul dalam kedua hubungan itu, dan hubungan objeknya,
mencintai, muncul di dalam keduanya, dan keyakinan serta fakta memiliki arah yang
sama. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi keyakinan akan salah. Dengan
begitu keyakinan akan salah jika arah faktanya berbeda (jika Inayah mencintai Andi)
atau jika salah satu istilah objeknya berbeda (jika Andi mencitai Romlah) atau jika
hubunga n objeknya berbeda (jika Andi membenci Inayah).
Meskipun Russell tampaknya begitu yakin atas teori yang disampaikan
tentang teori kebenaran, namun tampaknya ia tetap mengakui keterbatasan-
keterbatasan manusia dalam menggapainya. Menurutnya meskipun menurut
manusia terdapat suatu kebenaran namun ketepatan yang sempurna dalam ilmu
pengetahuan yaitu tentang kebenarannya tidak dapat dicapai. Baginya usaha
manusia yang mungkin dalam hal itu adalah terus menerus mengurangi keraguan-
keraguan kekaburan-kekaburan antara kebenaran dan kesalahan. Yang terjadi ialah
proses menuju pada kebenaran yang sempurna.134
3. Kebenaran menurut Charles Sanders Peirce (Pragmatisme)
Charles S. Peirce (1839-1914 M) merupakan bagian dari tokoh pragmatisme
Amerika, namun kemudian ia mengubah nama pragmatisme menjadi
pragmatisisme.135
Ia pada dasarnya bukan hanya sosok filosof, lebih dari itu ia juga
seorang saintis khususnya di bidang fisika yang banyak berkecimpung di
laboratorium. Di samping itu, ia adalah seorang yang mempunyai keyakinan moral
begitu kuat.136
Latar belakangnya sebagai fisikawan dan moralis tampaknya
mempengaruhi pemikirannya yang bercorak ilmiah dan etis.
Menurut Mustaqim, kebenaran oleh Peirce dibagi menjadi dua; Pertama,
kebenaran transendental (Trancendental Truth), yaitu kebenaran yang menetap pada
benda itu sendiri. Kedua, kebenaran kompleks (Complex Truth), yaitu kebenaran
dalam pernyataan. Kebenaran kompleks dibagi menjadi kebenaran etis atau
psikologis yaitu keselarasan pernyataan dengan apa ya ng diimani pembicara, dan
kebenaran logis atau literal, yaitu keselarasan pernyataan dengan realitas yang
didefinisikan. Semua kebenaran pernyataan ini harus diuji dengan konsekuensi
praktis melalui pengalaman.137
134
Bertrand Russell, Fakta, Kepercayaan, Kebenaran dan Pengetahuan ..., h. 75. 135
Richard, Teori-Teori Kebenaran ..., h. 117. 136
Titus, Smit dan Nolan, Persoalan-persoalan Filsafat,.., 341. 137
Peniel Maiaweng, “Manfaat Kebenaran Perbuatan: Suatu Analisis Terhadap
Ajaran Filsafat Pragmatisme”, Researchgate, April 2013, h. 8. Diakses pada 16 Agustus 2019
dari https://www.researchgate.net/publication/318056102
51
Bagi peirce, kebenaran tidak cukup hanya dianalisa menggunakan metode
ilmiah seperti disebutkan di atas. Lebih dari itu, kebenaran ilmu juga harus dapat
dipahami melalui interaksi sosial, karena itu merupakan keprihatinan komunitas.138
Pada akhirnya konsekuensi sosial ini menjadi kekuatan buat Pierce dalam rangka
menentukan kebenaran. Peirce kemudian membedakan antara keraguan dan
keyakinan. Orang yang yakin pasti berbeda dengan orang ragu minimal dari dua hal:
feeling and behavior. Orang yang ragu selalu merasa tidak nyaman dan akan
berupaya untuk menghilangkan keraguan itu untuk menemukan keyakinan yang
benar.139
Dalam pandangannya tentang teori kebenaran ia mengatakan bahwa
teori/pernyataan dapat dikatakan sebagai benar apabila teori tersebut mempunyai
manfaat. Maka untuk mengukur kebenaran suatu pernyataan ialah dengan cara
melihat fungsinya dalam kehidupan praktis. Penyataan atau pengetahuan dapat
dikatakan benar apabila ia dipercaya dapat memberikan kegunaan praktis dalam
kehidupan sehari-hari.140
Dalam hal ini, Seperti yang dikatakan Bacon bahwa
pengetahuan menjadi tidak berarti ketika ia tidak mampu mengubah manusia kepada
kehidupan yang lebih baik.141
Dalam hal ini, dampak positif menjadi justifikasi
kebenaran suatu pengetahuan.
Teori kebenaran pragmatisme Pierce ini jika dikaitkan dengan keyakinan
tampaknya menarik. Suatu keyakinan atau kepercayaan dapat dikatakan benar
selama ia dapat membawa hasil terbaik bagi kehidupan seseorang seperti dapat
meningkatkan kesuksesan dan lainnya. Namun apabila keyakinan itu justru
sebaliknya maka keyakinan itu adalah salah. Dari yang telah dipaparkan di atas
tampaknya dapat kita pahami bahwa teori kebenaran pragmatisme yang ditawarkan
oleh Charle S. Pierce ini bersifat relatif. Suatu pernyataan yang sama akan menjadi
benar dan salah dalam situasi dan kondisi berbeda yang membuat fungsi atau
manfaat dari suatu pernyataan atau teori itu juga berubah.
138
Rodliyah Khuza‟i, Dialog Epistemologi Mohammad Iqbal dan Charles S. Peirce
..., h. 88. 139
Mustakim, “Pragmatisme dalam Filsafat Kontemporer: Analisa atas pemikiran
Charles S. Peirce”, dalam al-Mabsut 3, No. 1, 2012, h. 11. 140
Fauziah Nurdin, “Kebenaran Menurut Pragmatisme Dan Tanggapannya
Terhadap Islam”, dalam Islam Futura 13, no. 2, Februari 2014, h. 192. 141
Nunu Burhanuddin, “Pemikiran Epistemologi Barat: dari Plati Sampai Gonseth”,
dalam Intizar 21, no. 1, Januari 2015, h. 137.
53
BAB III
LATAR BELAKANG MURTAḌÁ MUṬAHARĪ
A. Biografi
Sabara1 dan Maryam Shamsaei sepakat bahwa Murtaḍá Muṭahharī
adalah seorang pemikir tingkat tinggi, filsuf, ahli hukum dan seorang Islamolog
langka2 yang lahir pada tanggal 2 Februari 1920 M, bertepatan dengan 12
Jumādīl Ūlá 1228 H dan meninggal dunia pada 1 Mei 1997. Pertama kali ia
menghirup udara bumi tepatnya di daerah Fariman, dekat kota Mashhad, Iran.3
Mashhad merupakan salah satu kota yang dianggap suci oleh pengikut Syiah
Imāmiyah.4 Orang tua Murtaḍá merupakan seorang ulama Syiah terkemuka dan
dihormati, yaitu Shaykh Muḥammad Ḥusayn Muṭahharī.5 Muḥammad Ḥusayn
adalah orang pertama yang memperkenalkannya kepada ilmu pengetahuan. Ia
berada dalam bimbingan ayahnya sampai usia 12 tahun setelah kelahirannya.6
Muḥammad Ḥusayn Muṭahharī bukan hanya sekedar orang tua baginya,
tetapi juga menjadi seorang guru yang mempunyai perhatian cukup tinggi
terhadap pendidikan anaknya, sehingga ia selalu membimbing Murtaḍá dengan
baik.7 Keadaan tersebut merupakan suasana hidup di masa kecilnya. Murtaḍá
sejak lahir sudah berada di lingkungan keilmuan, maka tidak heran jika Misri A.
Muchsin meyakini bahwa Murtaḍá merupakan filosof besar yang sudah dibentuk
sejak ia lahir dan besar di tengah dan dalam praktek ajaran Syiah khususnya
Syiah Imāmiyah. Sosio-pemikiran keagamaan yang didapatkan olehnya
kemudian menjadikannya tumbuh sebagai penganut Syiah Imāmiyah yang
konsisten di kemudian hari.8
Pada tahun 1932 M Murtaḍá Muṭahharī belajar di madrasah tempat
kelahirannya yaitu Fariman,9 di sanalah ia mendapatkan ilmu tentang membaca,
1 Sabara, Pemikiran Tasawuf Murtaḍá Muṭahharī, Relasi dan Kesatuan antara
Intelektualitas (Ilmu), Spiritualitas (Iman) dan Moralitas (Akhlak), (Makasar: Balai
Penelitian dan Pengembangan Makasar, t.h), h. 150. 2 Maryam Shamsaei and Mohd Hazim Shahb, “Philosophical Study on Two
Contemporary Iranian Muslim Intellectual Responses to Modern Science and Technology”,
dalam International Journal Of Environmental & Science Education, vol. 12, no. 4, 2017, h.
881. 3 Haidar Baqir, Murtaḍá Muṭahharī Sang Mujahid, (Bandung: Yayasan Muṭahharī,
1998), h. 26. 4 Murtaḍá Muṭahharī, Kritik Islam terhadap Marxisme. Penerjemah Akmal Kamil,
(Jakarta: al-Huda Islamic Centre, 2005), h. 278. 5 Haidar Baqir, Murtaḍá Muṭahharī ..., h. 25.
6 Syamsuri, “Manusia Sempurna Perspektif Murtaḍá Muṭahharī”, Laporan
Penelitian Dosen, (Ciputat: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri
Jakarta, 2001), h. 8. 7 Dewan Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
1997), h. 313. 8 Misri A. Muchsin, Filsafat Sejarah dalam Islam Landasan Konsepsi dan
Prospektif, (Banda Aceh: ar-Raniry Press 2005), h. 154. 9 Sanusi Ismail, Filsafat Sejarah Wacana Tentang Kausalitas dan Kebebasan dalam
Kehidupan Kolektif, (Banda Aceh: ar- Raniry Press, 2012), h. 77.
54
menulis, surat-surat pendek al-Qur‟an dan pengantar sastra Arab.10
Tampaknya,
ilmu-ilmu yang didapatkan itulah yang kemudian menjadi bekal dan bahkan
mampu mempengaruhi perkembangan intelektualnya.
Pada periode berikutnya, terdapat beberapa figur yang turut mendidik
Muṭahharī di antaranya ialah Mirza Mahdi Syahidi Razavi, Ayatullah Khomaeni,
Ayatullah Boroujerdi, dan Ayatullah Muhammad Husain Ṭabāṭabā‟ī.11
Mirza
Mahdi Syahidi Razavi merupakan sosok yang memberikan ilmu tentang filsafat
tradisional. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar tersebut, ia kemudian
berpetualang ke Hawzah Mashhad untuk melanjutkan pelajaran agama. Tempat
itu adalah pusat pendidikan agama Syiah, di masanya. Di Hawzah Mashhad
tersebut, Muṭahharī telah menunjukkan kecerdasan dan keseriusan dalam upaya
mempelajari ilmu-ilmu Islam. Di sana, ia juga telah menunjukkan minat besar
terhadap filsafat dan Irfan. Selama di Mashhad, beliau banyak terinspirasi oleh
kepribadian seorang filsuf Islam tradisional ternama kala itu, Mirza Mehdi
Syahidi Razavi.12
Setelah itu, pada 1936 ia pindah ke kota Qom, yang merupakan pusat
intelektual dan spiritual Islam Syiah di Iran, ia belajar ilmu-ilmu keislaman dan
filsafat di universitas di sana. Ia belajar filsafat, hukum, sastra, fikih dan berbagai
disiplin ilmu lainnya.13
Murtaḍá Muṭahharī menunjukkan minat yang cukup besar
terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Ia mempelajari pemikiran
Aristoteles, Will Durant, Betrand Russel, Sigmud Freud, Alexis Carrel, Erich
Fromm, Einsten dan pemikiran-pemikiran tokoh Barat lainnya.14
Ketika Muṭahharī belajar di Qom, ia belajar di bawah bimbingan
Ayatullah Boroujerdi dan Khomeini.15
Muṭahharī mengikuti kuliah-kuliah
Ayatullah Boroujerdi (sebagai direktur lembaga pengajaran di Qom) mengenai
filsafat dan irfan. Muṭahharī mengenal lebih jauh pribadi Imam Khomeini di
lembaga ini, sebagaimana yang dipaparkannya:
"Ketika di Qom, aku menemukan pribadi yang kudambakan.
Kusadari bahwa dahaga jiwaku akan terpuasi oleh air mata air murni
pribadi itu. Meskipun aku belum menyelesaikan tahap-tahap awal
belajarku, dan belum memadai untuk mempelajari ilmu-ilmu rasional
(ma'qulat), kuliah-kuliah etika yang diberikan oleh pribadi tercinta itu
pada setiap Kamis dan Jum‟at yang tidak terbatas oleh etika dalam arti
10
Dewan Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
1997), h. 313. 11
Dedi Inwansyah, "Resonansi Pemikiran Pemimpin Islam Syiah dalam Dunia
Pendidikan Indonesia: Studi Tentang SMA Plus Muṭahharī”, dalam Akademika, vol. 19, no.
01, Januari-Juni 2014, h. 81. 12
Muhsin Labib, Filosof Sebelum dan Sesudah Mulla Shadra, (Jakarta: Lentera,
2005), h. 278. 13
Sanusi Ismail, Filsafat Sejarah Wacana Tentang Kausalitas dan Kebebasan
dalam Kehidupan Kolektif ..., h. 77. 14
Sanusi Ismail, Filsafat Sejarah Wacana Tentang Kausalitas dan Kebebasan
dalam Kehidupan Kolektif ..., h. 77. 15
Jalaluddin Rakhmat, Kata Pengantar dalam Murtaḍá Muṭahharī, Perspektif al-
Qur’an tentang Manusia dan Agama, (Bandung: Mizan, 1992), h. 8.
55
akademis yang kering, namun yang menyangkut ʻirfān dan perjalanan
spiritual. Kuliah-kuliah itu ekstase pada diriku, yang pengaruh-
pengaruhnya kurasakan sampai senin atau selasa berikutnya. Sebagian
kepribadian intelektual dan spiritualku terbentuk oleh pengaruh kuliah-
kuliah itu dan kuliah-kuliah yang lain yang kuikuti selama 12 tahun dari
guru spiritual itu".16
Guru lainnya di Qom adalah mufassir al-Qur‟an dan filosof yaitu
Ayatullah Sayyid Muḥammad Husein Ṭabāṭabā‟ī. Sebagian dari materi kuliah
Ṭabāṭabā’ī yang diikuti olehnya adalah filsafat materialisme dan al-Shifāʻ
karangan Ibnu Sīnā. Berkat kecerdasannya yang luar biasa, tradisi keilmuan
Barat dan Timur dikuasai oleh Muṭahharī.17
Khomeini merupakan guru yang mempunyai hubungan yang sangat
dekat dengannya. Sang Imam adalah pengajar muda yang mempunyai kedalaman
dan keluasan wawasan keislaman dan kemampuan menyampaikannya kepada
orang lain dengan sangat baik. Kehebatannyalah yang menjadikan pelajaran-
pelajaran Khomeini, terutama pelajaran mengenai irfan, meninggalkan bekas
yang amat kuat dalam hati Muṭahharī. Bahkan materi yang disampaikan
Khomeini itu masih terngiang-ngiang di telinganya sampai beberapa hari setelah
mendengarkannya.
Pada sekitar tahun 1946 M, imam Khomeini mulai memberikan kuliah
pada sekelompok kecil siswa, salah satunya adalah Muṭahharī di madrasah
Faiziyah mengenai dua teks utama filsafat asfār al-Arbaʻah karya Mulla Sadra
dan Syarhi man Zuma tulisan Mulla Hadi Sabsavari. Keikutsertaan Murtaḍá
dalam kelompok belajar ini berlangsung hingga tahun 1951 M, sehingga ia dapat
membina hubungan lebih dekat dengan Imam Khomeini. Pada tahun 1946, Imam
Khomeini memberikan kuliah resmi pertamanya mengenai fikih dan ushul
tentang bab hujjah-hujjah rasional dari jilid kedua Kifāyat al-Uṣūl-nya Akhund
Khurasani.18
Tidak hanya Khomeini yang menjadi gurunya. Bahkan ʻAllamah
Ṭabāṭabā‟ī yang juga merupakan ulama besar di masanya juga menjadi guru
favorit Muṭahharī di bidang filsafat dan irfan. Sedangkan pemikiran ʻAllamah
juga dipengaruhi kajian-kajian mengenai Nahj al-Balāghah. Nahj al-Balāghah
merupakan kumpulan wacana, pidato, surah-surah dan kata-kata bijak khalîfah
keempat dan imam pertama dalam madzhab Syiah, „Alī bin Abī Ṭālib.19
Murtaḍá Muṭahharī meninggalkan kota Qom pada tahun 1952 kemudian
menetap di Taheran, menikah dengan putri Ayatullah Ruhani.20
Di tempat
16
Haidar Baqir, Murtaḍá Muṭahharī ..., h. 29. 17
Haidar Bagir, Murtaḍá Muṭahharī ..., h. 32. 18
Haidar Baqir, Murtaḍá Muṭahharī ..., h. 31-32. 19
Haidar Baqir, Membincang Metodologi Ayatullāh Murtaḍá Muṭahharī,
(Yogyakarta: UGM, 2004), h. 2. 20
Haidar Baqir, Murtaḍá Muṭahharī ..., h. 29-30.
56
tersebut, ia belajar di bawah bimbingan Ayatullah Boroujerdi dan Khomeini.21
Tentunya kepindahan tersebut beralasan yang kuat.
Di antara faktor-faktor yang menjadikannya pindah ialah pertama, guru
yang menjadi curahan perhatiannya, Mirza Mehdi Syahidi Razawi wafat pada
tahun 1936. Kedua, Kemunduran yang dialami Hawzah Mashhad. Ketiga, adanya
tekanan-tekanan destruktif dari pemerintah tirani yaitu raja Reza Khan, terhadap
seluruh lembaga-lembaga ke-Islam-an, termasuk Hawzah Mashhad.22
Kerajaan
Persia kala itu menganggap bahwa eksistensi berbagai institusi Islam tersebut
dapat mengganggu stabilitas politis negara.23
Setelah meninggalkan kota Qom, Muṭahharī mengajar filsafat dan
teologi keislaman di Universitas Taheran dan Madrasah Yi Marvi, yang
merupakan salah satu lembaga pendidikan ternama di kota tersebut. Selain itu,
Muṭahharī juga aktif dalam organisasi-organisasi ilmiah. Pada tahun 1960, ia
mendirikan kelompok diskusi di bawah pengawasan Ayatullāh Talegani dan
Mahdi Bazargan. Organisasi ini menyelenggarakan kuliah-kuliah bagi
masyarakat kelas menengah seperti dokter, insinyur, dan lainnya. Hal ini
bertujuan untuk menyajikan relevansi dan kontekstualisasi Islam dengan
persoalan Islam kontemporer di samping untuk memancing munculnya ide-ide
reformasi dari ulama. Pada tahun 1965, Muṭahharī mendirikan Ḥusayniyah al-
Irsyad bersama Ali Syariati, Hossen Nasr. Dalam kelompok ini, Muṭahharī
menjabat sebagai Anggota Badan Pengarah, Dosen dan juga penyumbang artikel-
artikel. Akan tetapi, kelompok ini tidak berlangsung lama karena Muṭahharī
keluar dari kelompok ini disebabkan tidak adanya kecocokan pemikiran dengan
Ali Syariati.24
Muṭahharī juga aktif dalam kegiatan politik. Sejak masih mahasiswa di
Qom ia telah menjadi bagian dari anggota Fida'iyan al-Islam, organisasi Islam
militan di Iran yang berdiri pada tahun 1945. Ketika perjuangan melanda seluruh
Iran, pada tahun 1948-1950, Muṭahharī termasuk salah satu tokoh dan penggerak
pro kemerdekaan lewat Fida'iyah al-Islam. Pada 6 Juni 1963 M secara terang-
terangan Muṭahharī menunjukkan diri sebagai politikus dan intelektual yang
bersebrangan dengan Syah Pahlevi, penguasa Iran, sehingga dijebloskan ke
dalam penjara.25
Karena itu, Muṭahharī mempunya andil besar dalam pergerakan revolusi
Iran yang dipelopori oleh Imam Khomeini. Muṭahharī yang mendampingi sang
Imam ketika pulang dari pengasingannya di Paris, Prancis bahkan ia adalah
penasihat sekaligus tangan kanan sang Imam. Muṭahharī seorang ideolog dan
pemimpin spiritual kedua Republik Islam Iran setelah Khomeini. Ketika revolusi
Iran diproklamasikan pada 12 Januari 1979, Muṭahharī masuk sebagai anggota
21
Jalaluddin Rahmat, “Kata Pengantar”, dalam Murtaḍá Muṭahharī, Perspektif al
Qur’ān tentang Manusia dan Agama, (Bandung: Mizan, 1992), h. 8. 22
Muhsin, Filosof ..., h. 279. 23
Murtaḍá Muṭahharī, Mutiara Wahyu. Penerjemah Shaykh Alī al-Ḥamīd, (Bogor:
Cahaya, 2004), h. 155-156. 24
Editor A. Khudari Saleh, Pemikiran Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Jendela,
2003), h. 277. 25
Editor A. Khudari Saleh, Pemikiran Islam Kontemporer ..., h. 277.
57
dewan, namun tiga setengah bulan pasca proklamasi, ia terbunuh. Muṭahharī
meninggal pada 1 Mei 1979 akibat tembakan sekelompok teroris (Furqān)26
anti
Khomeini.27
Pengabdian Muṭahharī kepada revolusi Islam dihentikan secara brutal
terhadap dirinya yang mengakibatkan ia terbunuh. Riwayat tragedi ini bermula
pada 1972, Muṭahharī menerbitkan sebuah buku berjudul "'Ilah Girayish ba
Maddigari" (Alasan-Alasan Berpaling ke Materialisme), sebuah karya penting
yang menganalisa latar belakang historis materialisme di Eropa dan Iran. Selama
revolusi, ia menulis pengantar bagi edisi kedelapan buku itu, yang menyerang
penyimpangan-penyimpangan atas pemikiran Hafiz dan Hallaj yang terjadi
dalam beberapa golongan masyarakat Iran, dan menolak interpretasi-interpretasi
materialistik terhadap al-Qur‟an. Sumber interpretasi-interpretasi itu adalah
kelompok Furqān, yang berupaya menyangkal konsep-konsep asasi al-Qur‟an,
seperti transendensi ilahiah dan realitas akhirat. Dalam kasus-kasus semacam itu,
nada Muṭahharī selalu bersifat persuasif dan mengimbau, tidak berang ataupun
mengutuk. Ia malah mengajak Furqān dan kelompok-kelompok lain yang
berkepentingan untuk menanggapi tulisannya. Tanggapan mereka atas tulisannya
tak lain adalah penembakan atas dirinya.28
Ancaman untuk membunuh semua yang menentang mereka (kelompok
Furqān) termaktub dalam penerbitan Furqān. Setelah terbitnya edisi baru ilal-i
Girayish ba Maddigari, Muṭahharī tampaknya merupakan tanda kesyahidan
dirinya. Menurut kesaksian putranya, Mujtaba bahwa Muṭahharī terlepas dari
masalah-masalah duniawi pada saat menjelang tragedi tersebut. Ia kian
memperbanyak salat malam dan membaca al-Qur‟an. Ia juga bermimpi berjumpa
dengan Rasulullah Saw bersama Imam Khomeini.29
Pada tanggal 1 Mei 1997 M, Muṭahharī ditembak mati oleh pengikut
Furqān.30
Hamid Algar dalam bukunya menjelaskan Muṭahharī dibunuh ketika ia
pergi ke rumah Dr. Yadullah Sahabi bersama anggota-anggota lain dari Dewan
Revolusi Islam. Pada sekitar pukul 10:30 malam, ia dengan peserta lain bertemu
Ir. Katira'i, meninggalkan rumah Sahabi. Muṭahharī berjalan sendirian menuju
jalan kecil terdekat, tempat parkir mobil yang akan membawanya pulang,
Muṭahharī tiba-tiba mendengar suara asing memanggilnya. Ketika menengok ke
arah suara itu, sebuah peluru menembus kepalanya, masuk ke bawah telinga
kanan dan keluar di atas alis mata kiri. Ia meninggal hampir seketika. Meski
sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun tak ada lagi yang bisa dilakukan
26
Kelompok Furqān adalah kelompok yang menyatakan diri sebagai pendukung
suatu Islam Progresif, yang bebas dari apa yang mereka sebut "pengaruh menyimpang
ulama". Hamid Algar, “Hidup dan Karya Murtaḍá Muṭahharī”, dalam Haidar Bagir, Murtaḍá
Muṭahharī Sang Mujahid Sang Mujtahid ..., h. 45. 27
Hamid Algar, “Hidup dan Karya Murtaḍá Muṭahharī”, dalam Haidar Bagir,
Murtaḍá Muṭahharī Sang Mujahid Sang Mujtahid ..., h. 278. 28
Hamid Algar, Hidup dan Karya Murtaḍá Muṭahharī ..., h. 46. 29
Hamid Algar, Hidup dan Karya Murtaḍá Muṭahharī ..., h. 47. 30
Jhn L. Esposito, The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic Word,
diterjemahkan menjadi Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern,. Penerjemah Eva Y. N.,
dkk, jilid. 4, (Bandung: Mizan, 2001), h. 128.
58
selain berduka cita atasnya. Pada hari berikutnya, jasadnya disemayamkan di
rumah sakit, dan pada hari Kamis, di tengah-tengah perkampungan luas, jasadnya
dibawa untuk disalatkan, pertama di Universitas Taheran dan kemudian ke Qom
untuk dimakamkan, di sebelah makam Syaikh Abdul Karim Ha'iri.31
B. Latar Belakang Pemikiran dan Karyanya
1. Latar Belakang Pemikiran
Murtaḍá Muṭahharī merupakan sosok pemikir, ulama yang memiliki
kualitas dalam penguasaan keilmuannya. Bahkan Muhsin Labib mengatakan
bahwa Muṭahharī merupakan Salah satu ikon pemikiran filsafat produk Hawzah
di Qom yang mendunia. Bahkan ia menjadi lebih mendunia lagi setelah ia
wafat.32
Muṭahharī ialah sosok yang begitu cinta terhadap filsafat, teologi dan
tasawuf (irfan). Kecintaan itu lahir ketika ia berada dan belajar di Mashhad33
,
dan tertanam dalam dirinya sepanjang hidupnya dan membentuk pandangan
menyeluruhnya tentang agama.34
Guru di Mashhad yang menjadi perhatian khusus Muṭahharī ialah
seorang guru filsafat, Mahdi Syahidi Razavi.35
Mahdi bisa dikatakan sebagai
guru pertama Muṭahharī di bidang filsafat. Tokoh berikutnya yang menjadi
peracik pemikiran Muṭahharī adalah Imam Khomeini. Ia bertemunya ketika
berada di Qom36
. Di Kota inilah ia mendapat bimbingan dari Imam Khomeini
untuk menjadi pemimpin revolusi Islam. Imam Khomeini dan Muṭahharī sama-
sama menekuni semua segi ilmu pengetahuan tradisional, akan tetapi keduanya
tidak terjebak di dalamnya. Keduanya mengkaji Islam dengan wawasan luas,
yaitu Islam sebagai suatu sistem menyeluruh bagi kehidupan dan keimanan
dengan penekanan kepada segi-segi filosofis dan mistikal. Di samping itu,
keduanya menampakkan kesetiaan penuh kepada pranata keagamaan, yang
diwarnai oleh suatu kesadaran akan perlunya pembaharuan, suatu keinginan
akan perubahan sosial dan politik yang menyeluruh. Tidak hanya itu, langkah-
langkah keduanya juga disertai kesadaran akan strategi, waktu dan kemampuan
31
Hamid Algar, Hidup dan Karya Murtaḍá Muṭahharī ..., h. 47. 32
Muhsin Labib, Pemikiran Filsafat M.T Miṣbāḥ Yazdī, (Jakarta: Sadra Press,
2011), h. 57. 33
Mashhad adalah kota kedua terbesar di Iran dan merupakan salah satu kota suci
Syiah. Pada waktu Muṭahharī pindah ke sana, Mashhad merupakan sebuah wilayah yang
menjadi pusat ziarah dan belajar. Di tempat inilah ia mulai berkenalan dengan filsafat Islam
dan ilmu rasional. Muhsin Labib, Pemikiran Filsafat M.T Miṣbāḥ Yazdī, h. 57. 34
Hamid Algar, Hidup dan Karya Murtaḍá Muṭahharī ..., h. 26-27. 35
M. Said Marsaoly, “Memotret Muṭahharī Lebih Dekat: Sebuah Biografi”,
pengantar dalam Murtaḍá Muṭahharī, Mengapa Kita Diciptakan. Penerjemah Mustamin Al
Mandary, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2013), h. 4. 36
Qom adalah sebuah kota di Iran yang mendapat julukan kota sejuta ulama. Saat
ini Qom menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pendidikan Syiah terbesar di dunia. Diakses
pada 01 Oktober 2019 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Qom.
59
untuk menggapai ke luar lingkup kaum religius tradisional dan memperoleh
perhatian serta kesetiaan dari kaum berpendidikan sekuler.37
Imam Khomeini merupakan salah satu sosok yang mewarnai
pemikirannya terutama di bidang filsafat dan irfan (tasauf). Bahkan apa yang
sampaikan oleh Imam Khomeini membawa kesan begitu mendalam hingga
terngiang-ngiang dalam benaknya hingga beberapa Minggu setelah
mendengarkan pelajar darinya.38
Selain Imam Khomeini, Muḥammad Husein
Ṭabāṭabā‟ī juga merupakan guru yang berpengaruh padanya. Muṭahharī
mengikuti kuliah-kuliahnya mengenal al-Shifāʻ Ibnu Sīnā dari tahun 1950-1953,
Muṭahharī juga mengikuti pertemuan-pertemuan Kamis malam di bawah
bimbingannya. Materi pertemuan ini adalah filsafat materialis, yang menjadi
pilihan sekelompok ulama tradisional.39
Untuk mengetahui latar belakang pemikiran Muṭahharī, harus melihat
pada problem-problem yang dihadapinya semasa hidupnya yang penuh
perjuangan. Secara historis, bahwa kota Qom menjadi pusat keilmuan Muṭahharī
yang mengkristal sedikit demi sedikit. Pada waktu itu, kecondongan kepada
peradaban Barat telah berakar kuat dan melanda seluruh lapisan masyarakat.
Masyarakat menjauhi kebudayaan yang asli yang menjelma menjadi sebuah
masyarakat yang mengalami metamorfosis (perubahan bentuk) dan kehilangan
identitas. Tibalah sekarang masa panen penjajah dari apa yang ditanamnya sejak
awal yaitu pemerintahan dinasti Qajar.
Dampak-dampak kejahatan dan tipu daya berjangka panjang juga
dilakukan oleh penjajah mulai tampak secara berangsur-angsur, mengubah
bangsa pemberani pewaris peradaban tinggi menjadi bangsa lemah. Pusat
keagamaan menjadi kehilangan efektivitasnya dan slogan lama kolonial
mengenai pemisahan agama dari politik mulai mengakar dalam masyarakat. Itu
diakibatkan oleh tersebarnya propaganda-propaganda buruk anti para agamawan
dan ketidakberhasilan para agamawan itu sendiri dalam melaksanakan peranan
mereka dalam gerakan nasional. Itulah sebabnya Islam dijauhkan dari medan
perjuangan sosial hingga sebagian agamawan juga menyerah kepada pikiran ini.
Mereka mengira bahwa campur tangan dalam urusan-urusan politik dan sosial
tidaklah layak.40
Hal tersebut menyebabkan terbatasnya pikiran dan peradaban Islam
dalam kungkungan hukum-hukum dan masalah-masalah ibadah perseorangan
yang mengenainya ditulis risalah-risalah amaliah dan darinya dibuang masalah-
masalah jihad dan 'amar maʻrūf nahi al-munkar. Selain itu, Universitas menjadi
asing dari agama. Sebaiknya, agama dalam lingkungan universitas dianggap
pertanda kemunduran, dan penentangan terhadap kemajuan. Kebudayaan
mendominasi masyarakat, menyebabkan munculnya gerakan-gerakan
menyimpang. Maka tersebarlah ideologi-ideologi asing seperti marxisme dan
eksistensialisme, gerakan-gerakan nasionalisme dan peniruan bahkan Freudisme
37
Hamid Algar, Hidup dan Karya Murtaḍá Muṭahharī ..., h. 31. 38
Muhsin Labib, Pemikiran Filsafat M.T Miṣbāḥ Yazdī ..., h. 57. 39
Hamid Algar, Hidup dan Karya Murtaḍá Muṭahharī ..., h. 31-32. 40
Haidar Baqir, Murtaḍá Muṭahharī Sang Mujahid Sang Mujtahid ..., h. 54.
60
yang mengajarkan kebebasan seksual. Kemiskinan mencapai puncaknya hingga
segala macam pikiran diimpor dari Barat termasuk yang sudah tak lagi berharga
di masyarakat yang menciptakannya.41
Pemerintah Pahlevi juga mengalihkan perhatian masyarakat Islam Iran
dari pengaruh keislaman melalui kampanye-kampanye yang memupuk
nasionalisme masyarakat, menggencarkan propaganda melawan hukum-hukum
syariat Islam dan para ulama. Hal itu dilakukan tidak lain hanyalah untuk
memperkokoh kekuasaan Pahlevi.42
Namun para ulama Iran tidak hanya diam,
termasuk filosof Murtaḍá. Dalam situasi seperti inilah Muṭahharī terjun ke
medan kegiatan sosial. Ia memahami betul bahwa situasi-situasi ini saling
berkaitan satu sama lain. Muṭahharī melihat, di balik situasi ini terdapat sebuah
sistem yang cermat dan budaya yang bertumpu atas filsafat tertentu. Sehingga
Muṭahharī memahami bahwa tidaklah mungkin menanggulangi keadaan tersebut
kecuali dengan membutuhkan dasar ideologis dan filosofis serta kebudayaan
Barat yang mendominasi.43
Pemikiran Muṭahharī sangat bercorak filosofis. Muṭahharī merupakan
seorang pemikir Syi'i yang amat percaya kepada rasionalisme dan pendekatan
filosofis yang menandai mazhabnya. Muṭahharī membantah penyataan sebagian
pengamat yang menyatakan bahwa rasionalisme dan kecenderungan kepada
filsafat lebih merupakan unsur ke Persia-an dari pada keislaman. Muṭahharī
menunjukkan bahwa semuanya itu berada di jantung ajaran Islam, sebagaimana
ditunjukkan oleh al-Qur‟an, hadis Nabi dan ajaran para Imam.44
Mazhab Filsafat yang diikutinya adalah Mazhab filsafat Mulla Sadra
yaitu filsafat al-ḥikmat al-mutaʻāliyah (transendent theosophy) yang berupaya
memadukan metode-metode wawasan spiritualitas dengan metode-metode
deduksi filosofis.45
Kemampuannya yang mendalam dalam bidang filsafat sangat luar
biasa, sebagaimana yang dikatakan Jalaluddin Rakhmat: "Selagi menjadi
mahasiswa, Muṭahharī menunjukkan minat yang besar pada filsafat dan ilmu
pengetahuan modern. Gurunya yang utama dalam filsafat Ṭabāṭabā‟ī. Ia juga
mengenal aliran filsafat sejak Aristoteles sampai Sartre. Ia membaca sebelas
jilid buku berjudul Kisah Peradaban, Kelezatan Filsafat, dan buku-buku
lainnya karya Will Durant. Muṭahharī menelaah tulisan Sigmund Freud,
Bertrand Russel, Albert Einstein, Erich Fromm, Alexis Carrel, dan para pemikir
Barat lainnya.46
Selain itu, corak pemikiran filosofisnya tidak lepas dari perkembangan
pemikiran filsafat di Persia. Tentang pemikiran filsafat di Iran, Sayyed Hossein
Nasr menulis: "Filsafat Islam terus berkembang di Iran sebagai tradisi yang
41
Haidar Baqir, Murtaḍá Muṭahharī Sang Mujahid Sang Mujtahid ..., h. 54-55. 42
Haidar Baqir, Murtaḍá Muṭahharī Sang Mujahid Sang Mujtahid ..., h. 55. 43
Haidar Baqir, Murtaḍá Muṭahharī Sang Mujahid Sang Mujtahid ..., h. 55-56. 44
Muḥammad Nur, Murtaḍá Muṭahharī Kritik atas Moralitas Barat, (Kendal:
Penelitian Kompetitif Individual, 2016), h. 9. 45
Haidar Baqir, Murtaḍá Muṭahharī Sang Mujahid Sang Mujtahid ..., h.34. 46
Jalaluddin Rakhmat, Kata Pengantar dalam Murtaḍá Muṭahharī, Perspektif al-
Qur’an tentang Manusia dan Agama ..., h. 8.
61
hidup setelah apa yang dikenal dengan abad pertengahan, dan terus bertahan
sampai dewasa ini. Malahan, telah terjadi kebangkitan kembali filsafat Islam
selama masa dinasti Safawi, dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Mir Damad
dan Mulla Sadra. Kebangkitan yang kedua terjadi selama abad ke-13 H yang
diprakarsai oleh Mulla Ali Nuri, Haji Mulla Hadi Sabziwari, dan lain-lain.
Tradisi ini berlanjut secara kuat di Universitas-Universitas hingga masa
pemerintahan Pahlevi.”47
Muṭahharī mulai mempelajari filsafat materialis khususnya marxisme
setelah mempelajari ilmu-ilmu rasional. Pada tahun 1946 ia mempelajari
terjemahan-terjemahan Persia literatur Marxis yang diterbitkan oleh partai
Tudeh, organisasi Marxis besar di Iran dan ketika itu merupakan suatu kekuatan
penting di area politik. Selain itu, ia juga membaca tulisan Taqi Arani, ahli teori
utama partai Tudeh, maupun penerbitan Marxis dalam bahasa Arab yang
berasal dari Mesir. Awalnya Muṭahharī kesulitan memahami teks-teks ini,
sebab ia belum mengenal terminologi filsafat modern. Akan tetapi, ia terus
berusaha keras dengan menyusun sinopsis buku yang berjudul Elementary
Principles of Philosophy karya Georges Pulitzer, akhirnya ia menguasai seluruh
masalah filsafat materialis.48
Bagi Muṭahharī, filsafat merupakan suatu pola religiusitas yang
merupakan suatu jalan untuk memahami dan merumuskan Islam. Pandangan
Muṭahharī mengenai Islam bersifat filosofis tidak berarti menyiratkan bahwa ia
tidak memiliki spiritualitas atau ia menafsirkan dogma samawi secara filosofis,
atau ia menerapkan terminologi filosofis pada semua wilayah masalah
keagamaan. Akan tetapi, ia juga memandang peralihan ilmu pengetahuan dan
pemahaman sebagai tujuan dan manfaat utama agama. Oleh sebab itu, ia
memberikan keutamaan tertentu kepada filsafat di antara disiplin-disiplin yang
dikaji di lembaga keagamaan. Karena itu, ia sangat berbeda dengan ulama yang
lain yang menjadikan fikih segala-galanya dari kurikulum dan dengan kaum
modernis yang memandang filsafat sebagai cermin pengacauan Helenis ke
dalam dunia Islam.49
Karakteristik yang menjadi tipikal Muṭahharī adalah kedalaman
pengertiannya tentang Islam, keluasannya tentang filsafat, sains modern dan
keterlibatannya yang non-kompromis terhadap keyakinan dan ideologinya.
Karakteristik tersebut terjalin secara sistematis. Fuqahahnya dalam Islam dan
pengetahuannya tentang sumber peradaban Barat membuatnya menjadi ideolog
yang tangguh. Hal ini terlihat kerangka filosofis yang disebut wilāyatu al-
fāqih.50
Pemerintahan fakih (wilāyatu al-fāqih) adalah masalah yang segera
bisa disepakati dan tidak perlu dibuktikan lagi. Karena bagi orang yang sudah
47
Sayyed Hossein Nasr, Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern.
Penerjemah Luqman Hakim, cet, ke-1 (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), h. 195. 48
Hamid Algar, Hidup dan Karya Murtaḍá Muṭahharī ..., h. 32. 49
Hamid Algar, Hidup dan Karya Murtaḍá Muṭahharī ..., h. 34. 50
Murtaḍá Muṭahharī, Manusia dan Agama: Membumikan Kitab Suci ..., h.15.
62
tahu syari‟at Islam tanpa ragu akan menerima wilāyat al-fāqih . Adapun
wilāyatu al-fāqih ditegakkan atas empat prinsip dasar yaitu:51
Pertama: Allah adalah hakim mutlak pada alam semesta dan segala
isinya termasuk manusia yang ditempatkanNya di bumi, Allah merupakan
penguasa tunggal bagi umat Islam.
Kedua: Kepemimpinan manusia (qiyādah bashariyah) yang
mewujudkan kepemimpinan Allah di bumi adalah para Nabi. Para nabi
menyebarkan dan melaksanakan hukum Allah sejak Nabi Adam sampai Nabi
Muḥammad SAW.
Ketiga: Garis imāmah melanjutkan garis kenabian dalam memimpin
umat. Untuk menjalankan kepemimpinan ilahiah diperlukan manusia-manusia
suci yang fāqih tentang syariat Islam serta mewarisi perjuangan Rasulullah
SAW. Menurut paham Syiah bahwa ada 12 imam yang maʻṣūm setelah Nabi
Muḥammad wafat. Salah satu dari para imam tersebut saat ini dalam keadaan
ghaib akan tetapi suatu saat nanti akan kembali sebagai Imam Mahdi al-
Muntaẓar.
Keempat: Pada saat Imam ghaib maka kepemimpinan dilanjutkan oleh
para fuqaha. Pada mereka dipercayakan kepemimpinan atas umat.
Menurut 'Ain Najaf dalam kitab Qiyādatul ʻUlamā wal Ummah bahwa
tugas dan kewajiban ulama seperti Muṭahharī dalam kerangka wilāyat al-fāqih
sangatlah berat karena memiliki tugas-tugas yang berat yaitu:52
1. Tugas intelektual
2. Tugas bimbingan keagamaan
3. Tugas komunikasi dengan umat
4. Tugas menegakkan syiar Islam
5. Tugas mempertahankan hak-hak umat
6. Tugas berjuang melawan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin.
Muṭahharī menyadari tugas berat yang harus ia emban untuk umat
bangsanya (Iran). Muṭahharī berjuang dengan semangat yang luar biasa dengan
dijiwai falsafah wilāyat al-fāqih ia merasa perlu menyelamatkan bangsanya dari
ideologi Barat yang menurutnya berbahaya. Ia mengkritik ideologi Barat seperti
Marxisme, eksistensialisme, dan kapitalisme yang ia anggap menyimpang dari
nilai-nilai etika Islam.53
Maryam Shamsaei dalam tulisannya bahkan mengatakan bahwa Pada
saat Muṭahharī hidup, berkembang dua kelompok pemikiran Islam yang
berbeda bahkan bertentangan. Golongan-golongan tersebut di antaranya ialah
tradisionalis, modernis. Masing-masing golongan saling menentang satu sama
lainnya. Tradisionalis mencoba menolak berbagai pemikiran dari Barat,
termasuk konsep kebenaran dari Barat. Mereka mengatakan bahwa segala
produk yang datang dari Barat bertentangan dengan Islam. Islamisasi pemikiran
Barat tak dapat dilakukan karena keduanya merupakan dua hal yang tak
mungkin bisa disatukan. Para modernis menentang dan menolak berbagai
51
Murtaḍá Muṭahharī, Manusia dan Agama: Membumikan Kitab Suci ..., h. 17. 52
'Ain Najaf, Qiyādatul ʻUlamā wal Ummah, (Taheran: Hikmah, t. th), 17. 53
Muḥammad Nur, Murtaḍá Muṭahharī Kritik atas Konsep Moralitas Barat, h. 13.
63
pandangan tradisionalis. Mereka meyakini bahwa modernitas tidak dapat digali
dari teks-teks agama, oleh karena itu agama harus mengambil keputusan
dengan memperbaharui dan menyesuaikan dengan pemikiran modern.
Pemikiran Barat modern tidak semua bertentangan dengan Islam, maka umat
Islam bisa mengambilnya tanpa membahayakan Islam. Namun, Muṭahharī
mempunyai pandangan-pandangan berbeda. Ia justru memadukan antara
modernitas dengan tradisional. Dengan kata lain, mereka mencoba menemukan
kebutuhan dan makna baru dunia modern dalam teks-teks agama lama dan
menyiratkan bahwa konsep-konsep baru, memang ada dalam konteks agama
jauh sebelum peradaban Barat muncul.54
2. Karya-karyanya
Murtaḍá Muṭahharī cukup produktif dalam menghasilkan karya. Ia
mempunyai karya yang cukup banyak. Karya-karyanya baik hasil ceramahnya
maupun tulisannya mencapai lebih dari 200 karya dalam berbagai bidang
seperti filsafat, kalam, sosiologi, sejarah, antropologi dan etika.55
Tulisan
tersebut terdiri dari tulisan sendiri dan juga banyak akumulasi dari pidato-
pidatonya yang kemudian diterbitkan menjadi buku.
Di antara buku-buku karya Murtaḍá Muṭahharī di antaranya ialah:
a. Bidang Filsafat
Muqaddimah bar Jahan Bihi al- Islam, (Muqaddimah Pandangan
Dunia Islam), sebuah karya yang berisikan kumpulan dari tujuh pembahasan
mengenai pandangan dunia Islam tentang manusia, makna dan tujuan
hidupnya, hubungannya dengan Allah SWT dan alam semesta, peranannya
dalam masyarakat, sejarah dan sebagainya.56
Asyna'iba Ulum al-Islam t.p. (Pengantar Ilmu-Ilmu Islam. 2003).
Buku ini berisi telaah inklusif tentang pokok-pokok berbagai cabang ilmu-
ilmu Islam, seperti; Ushul Fikih, Hikmah Amaliah, Fikih, Logika, Kalam,
Irfan, dan Filsafat.57
Usul Falsafah wa Rawisy Riyalism (Prinsip Filsafat dan Aliran
Realisme), karya ini merupakan buku filsafat Muṭahharī yang terpenting.58
Al-ʻAdl al-Ilâhi (Qom, 1981). Dalam buku ini, Muṭahharī melakukan
eksplorasi atas tema penting dalam khazanah tentang ilmu-ilmu keislaman,
sekaligus mendemonstrasikan wawasan luasnya untuk membuktikan
penyataan bahwa keadilan merupakan sejenis "pandangan dunia" (world
view). Dalam buku ini ia juga mengkaji keadilan ini berdasarkan pendekatan
naqliah maupun aqliah dan menunjukkan betapa tema keadilan ini merupakan
rahasia sumber sejati dalam pemikiran dunia Islam. Kemudian diterbitkan
54
Maryam Shamsaei, “Two Iranian Intellectuals: Ayatollah Morteza Motahari and
Dr. Abdol-Karim Soroush and Islamic Democracy Debate”, dalam IOSR Journal of
Humanities and Social Science, vol. 1, no. 2, 2012, h. 30. 55
Mulyadi Kertanegara, Nalar Religius, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 280. 56
Abdillah Hasan, Tokoh Mashur Dunia Islam, (Surabaya: Jawara, 2004), h. 299. 57
Nihaya, Sinergitas Filsafat dan Teologi Murtaḍá Muṭahharī ..., h. 112. 58
Nina Arnando, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h.
135.
64
dalam bahasa Indonesia pada tahun 1992 dengan judul keadilan Ilahi: Atas
Pandangan Dunia Islam.59
Al-Fitrah (Taheran, 1410 H). Buku ini diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia dengan judul Fitrah dan diterbitkan pada tahun 1998. Buku
ini memaparkan dengan sangat jelas tentang pemahaman jati diri manusia.
Selain itu, dalam buku ini juga memberikan jawaban mendasar atas berbagai
pertanyaan yang menyangkut keberagaman.
Falsafah e-ahkhlak (Falsafah Akhlak). Buku ini menjelaskan tentang
korelasi antara filsafat, agama dan akhlak, selain menjelaskan landasan akhlak
dalam Islam, Muṭahharī juga menjelaskan bagaimana pandangan Filosof
Barat terhadap akhlak.
b. Tasawuf
Khatemiat t.p (terjemah Indonesia Kenabian Terakhir, 2001).
Dalam buku ini Muṭahharī membedah secara khas, analitis, kritis akurat, dan
komprehensif membungkam keraguan bagi mereka yang meragukan posisi
nabi Muḥammad Saw di tengah segelintir nabi yang membawa risalah dan
tugas khas serta ribuan nabi yang tak dikenal lainnya yang datang tanpa
membawa risalah. Peran imam dan ulama sebagai pewaris nabi di dalam buku
ini juga dibahas dan ditempatkan pada posisi benar.
Dastane Rastan (Cerita Orang Bijak). Buku ini merupakan salah
satu karya terbaik Muṭahharī di Iran pada tahun 1965. Muṭahharī membahas
kumpulan cerita orang saleh yang dikutip dari berbagai sumber keislaman
seperti hadis, sejarah para Imam, dan para tokoh Islam lainnya.60
c. Fikih
Nizamu al-Huquqi al-Mar'ah fi al-Islam (t.p) dalam penerjemahan
Inggris The Right of Women in Islam (Taheran 1981). Buku ini sudah
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Duduk Perkara
Poligami dan diterbitkan pada tahun 2007. Dalam buku ini, Muṭahharī
menyajikan beberapa topik pembahasan seputar hak-hak wanita dalam Islam,
di antaranya mengenai soal warisan, lamaran, mahar, nafkah, poligami dan
sebagainya dengan gayanya yang khas dan analitis, kritis, akurat, dan
komprehensif. Muṭahharī menjelaskan pula betapa syariat Islam betul-betul
sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, dan mengomentari betapa
gagasan-gagasan Barat hanyalah propaganda, palsu dan omong kosong.
Mas'alah al-Hijab (Taheran1407 H). Buku ini telah diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia menjadi Wanita dan Hijab, 2008. Pembahasan dalam
buku ini berisi tentang uraian Muṭahharī tentang masalah hijab, yang mana
secara keseluruhan buku ini membahas lima persoalan penting seputar hijab,
yaitu perintah mengenakan hijab,filsafat hijab, berbagai protes dan kritikan,
dan batas-batas hijab dalam Islam. Dalam buku ini Muṭahharī mengulas
59
Nihaya, “Sinergitas Filsafat dan Teologi Murtaḍá Muṭahharī”, dalam Sulesana,
vol. 8. no 1, 2013. h. 112. 60
Juliawati, “Esensi Manusia dalam Perspektif Murtaḍá Muṭahharī”, (Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018), h. 24.
65
dengan gayanya yang khas dan memaparkan dengan lengkap segala yang
berkaitan dengan tema tersebut.
C. Peran Murtaḍá Muṭahharī dalam Pemikiran Islam
Murtaḍá Muṭahharī merupakan seorang pemikir yang mengabdikan
hidupnya untuk perjuangan ideologi dan politik.61
Selain itu, ia juga seorang
cendekiawan muslim yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas tentang
berbagai hal. Syamsuri menyebutkan bahwa ia adalah intelektual muslim yang
taat beragama, moderat, dan terbuka serta senantiasa berkeinginan untuk
mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir generasi muda Islam Iran
dan meningkatkan kualitas pendidikan mereka.62
Pada tahun 1332 pemerintah yang berkuasa melakukan propagandanya
secara masif untuk melawan hukum-hukum Islam. Sehingga Muṭahharī menulis
berbagai karya yang membahas masalah-masalah fundamental berbagai
permasalahan Islam dalam rangka untuk mencegah meluasnya kerusakan.
Contoh upaya-upayanya ialah tentang masalah hak-hak wanita yang digembor-
gemborkan oleh orang-orang yang berambisi politik sehingga memenuhi media
sosial untuk mengubah pemikiran para pemuda. Untuk itu, Muṭahharī
memberikan ceramah-ceramah lewat khotbahnya dan kedua bukunya yang
berjudul Hak-Hak Wanita dalam Islam dan Hijab.63
Karya tentang hijab tersebut
ditulisnya tepat pada 1347 M di kala pemerintah menghina hijab untuk
menjadikan muslimah sebagai barang dagangan dalam melayani syahwat pria
serta menjauhkah masyarakat dari nilai-nilai Islam dan mengikuti tren Barat.
sesungguhnya karya tentang hijab merupakan suatu respons terhadap realitas
dalam rangka mengembalikan umat Islam pada ajaran Islam. Ia menulis dalam
buku tersebut:
"Ketelanjangan adalah penyakit zaman ini. Cepat atau lambat,
ketelanjangan itu sendiri akan menunjukkan tanda-tanda penyakitnya.
Meskipun kita meniru Barat dengan taklid buta, orang-orang Barat yang
lebih dahulu dari kita dalam bidang ini akan menunjukkan hakikat
ketelanjangan ini. Tetapi, saya khawatir sudah akan terlalu terlambat
bila kita menunggunya.”64
Selain itu, untuk menjauhkan Islam dari masyarakat Iran, pemerintah
Iran membangkitkan nasionalisme dan rasialisme. Dengan membangkitkan
keduanya, pemerintah berharap langkah tersebut akan melemahkan semangat
keagamaan rakyat Iran. Pemerintah memaparkan masalah kemandirian
kebudayaan asli Iran dan terpisahnya dari Islam, serta perjuangan bangsa Iran
dalam melindungi warisan budayanya dari pengaruh kebudayaan Islam.
Muṭahharī menanggapi soal ini melalui tulisannya yang berjudul Pelayanan
61
Haidar Bagir, Murtaḍá Muṭahharī Sang Mujahid, (Bandung: Yayasan Muṭahharī,
1988), h. 56-58. 62
Syamsuri, “Manusia Sempurna Perspektif Murtaḍá Muṭahharī” ..., h. 15. 63
Haidar Bagir, Murtaḍá Muṭahharī Sang Mujahid ..., h. 58. 64
Haidar Bagir, Murtaḍá Muṭahharī Sang Mujahid ..., h. 62.
66
Timbal Balik antara Islam dan Iran. Muṭahharī memaparkan bahwa rencana
jahat penguasa untuk mengikis keislaman rakyat Iran dan menggantinya dengan
nasionalisme. 65
Dalam masa itu, pembakaran warisan-warisan kultural dan ilmiah Iran
oleh bangsa Arab ketika menaklukkan Iran menjadi obyek pembicaraan di
media sosial sehingga Muṭahharī menulis kitab Pembakaran Kitab-Kitab di Iran
dan Alexandria. Ia membahas dan membuktikan bahwa semuanya itu adalah
dusta. Ia akhir tulisannya ia mengatakan:
"sesungguhnya propaganda pembakaran kitab-kitab di Iran dan
Alexandria secara berangsur-angsur telah menjadi suatu alat untuk
menyerang Islam. Dibalik itu semua terdapat taktik penjajah. Penjajah
tidak akan berhasil di bidang politik maupun ekonomi, kecuali bila ia
berhasil dalam penjajahan budaya. Faktor pertama untuk keberhasilan
dalam hal itu adalah menghilangkan hubungan rakyat dengan
kebudayaan dan kebudayaan asli mereka. Lewat pengalamannya,
penjajah telah memahami dan meyakini bahwa kebudayaan yang
diandalkan dan ideologi yang dibanggakan oleh masyarakat adalah
kebudayaan dan ideologi Islam.”66
Ketika pemikiran Barat tersebar di antara orang-orang yang
menjalankan agama. Muncul serangan-serangan terhadap pemikiran filsafat
untuk memperkenalkan logika Barat sebagai alat mengetahui isi al-Qur‟an.
Sehingga untuk menghadapi hal tersebut, Muṭahharī menulis kitab Ushul
Falsafah untuk menerangkan tentang filsafat Islam. Ia menjelaskan keotentikan
kandungan filsafat Islam dibandingkan filsafat Barat.67
Selain itu, gerakan serupa juga dilakukan dengan menggunakan
serangan melalui ideologi Marxisme. Muṭahharī menghadapinya dengan
perlawanan logis terhadap pokok-pokok pikiran Marxis yang merupakan
sumbernya. Itulah sebabnya ia lebih memperhatikan filsafat Marxisme daripada
lainnya. Muṭahharī sangat memahami paham Marxisme dikarenakan
pengetahuannya yang sangat luas terhadap filsafat Eropa. Ia menjelakan ide-ide
baru dalam pembahasan dan kritik filosofisnya terhadap Marxisme. Terdapat
pidato-pidato dan artikelnya yang membahas khusus materialisme dan
marxisme. Tidak hanya itu, Muṭahharī memulai perjuangannya melawan
Marxisme dengan bukunya Ushul Falsafah. Ia menghabiskan waktu untuk
meneliti Marxisme, ia mengetahui perbedaan Marxisme dari filsafat ilahiah.68
65
Haidar Bagir, Murtaḍá Muṭahharī Sang Mujahid ..., h. 59. 66
Haidar Bagir, Murtaḍá Muṭahharī Sang Mujahid ..., h. 63. 67
Haidar Bagir, Murtaḍá Muṭahharī Sang Mujahid ..., h. 72. 68
Haidar Bagir, Murtaḍá Muṭahharī Sang Mujahid ..., h. 79.
67
Sebelum revolusi, masyarakat Iran tidak memiliki konsep mengenai
pusat-pusat ilmiah keagamaan. Padahal pada saat itu, terjadi penyebaran
ideologi menyesatkan di tengah masyarakat seperti ajaran bahwa setiap orang
yang memiliki al-Qur‟an, terjemahannya dan sebuah kamus diperboleh untuk
menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an dan menerangkan hukum-hukum syariat. Hal
ini oleh Muṭahharī dipandang sebagai suatu hal yang menimbulkan masalah
besar. Oleh karena itu, untuk mengenalkan ilmu-ilmu Islam, ia menulis buku
yang berupaya menerangkan sesederhana mungkin pokok-pokok dan tema-tema
bangunan pemikiran Islam yang terdiri dari filsafat, kalam, teologi, logika, ushul
fikih, irfan, dan akhlak. Hal tersebut dapat mencegah penyimpangan yang timbul
akibat keengganan merenung dan ketidakmampuan pemikiran, di samping
menguatkan bangunan-bangunan pemikiran dan keyakinan.69
Muṭahharī lahir pada kondisi yang tepat, yaitu masa di mana ajaran
Islam mendapatkan serangan yang bertubi-tubi baik dari aspek pemikiran
maupun politik. Pada kondisi tersebut, Muṭahharī hadir untuk melawan serangan
untuk mengembalikan pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam yang
sesungguhnya. Pada perjuangan tersebut, Muṭahharī telah menghibahkan
pemikiran, jiwa, raga bahkan nyawanya demi Islam. Hal tersebut tampak pada
kegigihannya berjuang tanpa takut pada siapapun, bahkan ia ditembak mati oleh
musuhnya.
69
Haidar Bagir, Murtaḍá Muṭahharī Sang Mujahid ..., h. 80-81.
69
BAB IV
KONSTRUKSI TEORI KEBENARAN MURTAḌÁ MUṬAHARĪ
A. Pandangan tentang Kebenaran
1. Pandangan Murtaḍá Muṭahharī tentang Korespondensi, Koherensi
Mencari kebenaran1 bagi Murtaḍá adalah fitrah. Pencarian kebenaran
menurutnya lahir karena dorongan kesadaran diri. Kesadaran diri membuat
seseorang mendambakan kebenaran.2 Kesadaran diri seseorang dalam kaitannya
dengan dunia yaitu dari mana, di mana, dan ke mana akan mendorongnya untuk
menemukan posisi dirinya dalam dunia. Ia akan menyadari dan menemukan bahwa
ia hanyalah satu bagian kecil saja dari suatu keseluruhan besar bernama dunia.
Seseorang akan melihat bahwa ia bukanlah suatu pulau merdeka: ia, sebaliknya tak
merdeka: ia tidak datang, hidup dan meninggal sekehendak dirinya. Seseorang
akan berusaha mengidentifikasikan posisinya dalam suatu keseluruhan semacam
itu. Kesadaran tersebut oleh Ali dikatakan sebagai penyemangat perjuangan yang
paling sejati dan paling sublim untuk menemukan kebenaran. Jenis kesadaran
inilah yang mampu membangkitkan seseorang ke arah pengetahuan dan
kebenaran, yang memberi seseorang kesentosaan dan jaminan dalam tindak, serta
yang menggelisahkan seseorang dengan nyala api keraguan dan ketidakpastian.3
Berbagai teori kebenaran telah lahir di berbagai belahan dunia, baik di
Barat maupun di dunia Islam, namun sebagian teori kebenaran bersifat parsial.
Murtaḍá Muṭahharī menolak segala bentuk reduksi kebenaran. Pandangan-
pandangan ekstrim pada satu teori kebenaran menjadikan definisi dan pemahaman
terhadap kebenaran mengalami keterbatasan, maka seseorang yang melakukan hal
tersebut, ia tidak akan mencapai kebenaran yang sempurna. Seperti yang dilakukan
oleh para filosof Barat seperti Bertrand Russel. Bertrand Russel menolak
kebenaran yang berlandaskan pada objek yang tidak tampak, karena sesuatu yang
tidak tampak, dianggap olehnya sebagai sesuatu yang tidak berguna.4 Murtaḍá
tidak hanya menyudutkan filosof Barat, ia pun mengkritik siapa pun5 yang
menolak tiga kebenaran6 yang ditawarkan olehnya. Kebenaran yang hanya
1 Kebenaran merupakan hal yang fundamental, maka dari itu menerima kebenaran
oleh Murtaḍá dijadikan sebagai suatu syarat untuk menjadi seorang muslim. Nur Idam
Laksono, “Tasawuf untuk Kemanusiaan: Kajian terhadap Konsep Fitrah Murtaḍá
Muṭahharī”, dalam Attanwir, v. 05, no. 02, September 2015, h. 22. 2 Murtaḍá Muṭahharī, Filsafat Agama dan Kemanusiaan. Penerjemah Arif Maulawi,
(Yogyakarta: Rausyanfikr, 2013), h. 123. 3 Murtaḍá Muṭahharī, Manusia dan Agama. Penerjemah Haidar Bagir, (Bandung:
Mizan, 2007), h. 175. 4 Nur Idam Laksono, “Tasawuf untuk Kemanusiaan: Kajian terhadap Konsep Fitrah
Murtaḍá Muṭahharī”, dalam Attanwir, vol. 05, no. 02, September 2015, h. 27. 5 Siapa pun di sini merujuk kepada seluruh manusia yang hanya menerima salah
satu dari kebenaran termasuk intelektual muslim jika memang ia tidak menerima kebenaran
secara utuh. 6 Tiga kebenaran yang dimaksud ialah kebenaran intuitif, kebenaran rasional dan
kebenaran empiris. Baginya ketiga kebenaran tersebut adalah kebenaran yang benar-benar
benar.
70
menerima satu kebenaran (dari ketiga kebenaran) adalah oleh Murtaḍá dikatakan
sebagai kebenaran persial. Ketika teori kebenaran yang dianut kemudian menolak
teori kebenaran lain padahal teori yang ditolak tersebut juga merupakan kebenaran
hakiki, maka teori kebenaran tersebut menjadi salah.
Bagi Murtaḍá kebenaran7 merupakan persesuaian antara pengetahuan
dengan hakikat sebagaimana adanya atau menalar sebagaimana seharusnya.
Kebenaran merupakan pengetahuan yang sesungguhnya tentang suatu hal seperti
tentang alam, benda dan wujud lainnya. Kemudian ia menguatkan dengan sabda
Nabi, “ya Allah, perlihatkan kepadaku segala sesuatu sebagaimana yang
sesungguhnya”.8 Kebenaran itu ada pada sejauh mana subjek mempunyai
pengetahuan mengenai objek.9 Dalam kesempatan ini Murtaḍá tampak tidak
membatasi cara dan objek kebenaran, namun yang jelas ia mensyaratkan
pengetahuan hakiki tentang suatu hal. Tampak bahwa teori kebenaran Murtaḍá
sangat terbuka dan akomodatif terhadap berbagai teori kebenaran yang ada.
Murtaḍá sepertinya ingin mengolaborasikan banyak teori kebenaran yang
kontradiktif baik di Barat maupun di dunia Islam.
Dugaan penulis kemudian diperkuat oleh berbagai teori yang diungkapkan
Murtaḍá dalam beberapa bukunya. Dalam buku “Manusia dan Alam Semesta”,
Murtaḍá memberikan penegasan bahwa kebenaran merupakan persesuaian antara
persepsi tentang segala sesuatu yang didapatkan melalui indra dan akal, dengan
realitas eksternal.10
Jika pembawa kebenaran tidak sesuai dengan realitas11
eksternal, maka ia adalah salah. Kesesuaian ini oleh Murtaḍá disebut sebagai
haqīqah (kebenaran hakiki), sementara yang tidak sesuai disebut khaṭa’
(kesalahan).12
Dalam penjelasan ini, kebenaran ia asosiasikan dengan teori
7 Kebenaran bagi Murtaḍá adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga ia
mewanti-wanti agar kebenaran dijaga dengan baik dan tidak disalahgunakan. Seseorang oleh
Murtaḍá diminta untuk tidak pernah menyembunyikan kebenaran demi kepentingan diri
sendiri. Namun ia memperbolehkan menyembunyikan kebenaran demi kebenaran itu sendiri.
Jika kebenaran dimungkinkan akan disalahgunakan, maka hendaknya disembunyikan.
Penyembunyian kebenaran ini tidak dikatakan sebagai perbuatan bohong, karena Murtaḍá
menilai kebohongan merupakan perbuatan tidak benar. Jadi kegiatan berbohong adalah
dilarang, namun menyembunyikan kebenaran tidaklah dilarang. Yang dimaksud
menyembunyikan di sini ialah adakalanya kita diam ketika mengucapkan kebenaran akan
mengakibatkan keburukan meningkat. Murtaḍá Muṭahharī, Teologi dan Falsafah Hijab,
(Yogyakarta: Rausyanfikr Institute, 2013), h. 113. 8 Murtaḍá Muṭahharī, Fitrah: Menyingkap Hakikat, Potensi dan Jati Diri Manusia.
Penerjemah H. Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 71. 9 Suparlan Suhartono, Filsafat Ilmu Pengetahuan: Persoalan Eksistensi dan
Hakikat Ilmu Pengetahuan, (JogJakarta: Ar Ruzz Media, 2005), h. 82. 10
Murtaḍá Muṭahharī, Manusia dan Alam Semesta. Penerjemah Ilyas Hasan,
(Jakarta: Lentera Basritama, 2002), h. 51. 11
Realitas mempunyai berbagai pandangan yang berbeda. Materialisme
memandang, realitas sejati hanyalah yang bersifat materi. Rasionalisme memandang realitas
sejati adalah yang bersifat rasional. Namun pandangan Murtaḍá tentang realitas akan dibahas
dalam bagian khusus. 12
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Filsafat Islam: Filsafat Teoritis dan Filsafat
Praktis. Penerjemah M. Ilyas, (Yogyakarta: Rausyanfikr, 2003), h. 71-72.
71
kebenaran korespondensi, di mana kebenaran diukur oleh seberapa besar
kesesuaian pembawa kebenaran dengan realitas yang ada.
Murtaḍá menegaskan bahwa persesuaian pembawa kebenaran dengan
realitas eksternal tidak selalu menjadi penentu kebenaran. Persesuaian antara
pembawa kebenaran dengan realitas eksternal tidak selamanya dapat mengukur
kebenaran. Tolok ukur tersebut hanya bisa digunakan pada permasalahan yang
bersifat indrawi, alamiah dan eksperimental. Dalam masalah yang bersifat indrawi
seperti ilmu kedokteran, teori kebenaran ini dapat digunakan. Misalnya terdapat
teori yang mengatakan bahwa A merupakan penyebab kanker. Jika di alam
objektif sesuatu benar-benar dapat menyebabkan timbulnya penyakit kanker, maka
pengetahuan itu sama dengan objek realitas eksternal, tetapi jika tidak maka
pengetahuan itu adalah pengetahuan yang salah dan tidak semua pengetahuan
memiliki bentuk seperti itu.13
Murtaḍá mengatakan bahwa teknik pengujian
kebenaran menggunakan korespondensi seperti yang dijelaskan di atas tersebut
tidak dapat diterapkan pada persoalan yang bersifat rasional. Padahal menurutnya,
persoalan rasional merupakan salah satu pengetahuan yang kebenarannya tidak
dapat diragukan.
Contoh perkara rasional yaitu luas setengah lingkaran adalah sekian, tidak
mempunyai realitas eksternal seperti yang terjadi pada ilmu kedokteran. Dalam hal
pengetahuan rasional ini ialah kebenarannya dapat dikatakan sebagai kesesuaian
antara alam mental dengan alam mental itu sendiri.14
Yakni kebenaran rasional
merupakan suatu kebenaran yang bersesuaian dengan hukum-hukum rasional
lainnya yang telah diterima kebenarannya. “Diterima kebenaran” dipahami oleh
Amsal Bakhtiar sebagai hal yang telah disepakati bersama sebagai suatu
kebenaran, terutama oleh komunitas matematika.15
Pada permasalahan rasional
seperti ini prinsip korespondensi menjadi tidak berarti, ia tidak dapat menentukan
kebenaran yang bersifat rasional, karena hal semacam ini tidak berada di luar dari
diri kita. Sesuatu yang bersifat rasional berada dalam diri kita.
Kesesuaian antara pembawa kebenaran dengan realitas ternyata tidak juga
menjamin kebenaran yang sesungguhnya. Pendekatan materi semata dan
pendekatan rasional semata dalam kebenaran telah terbukti melakukan penyesatan-
penyesatan, seperti yang telah dilakukan oleh empirisme dan materialisme. Maka
Murtaḍá menambahkan bahwa kebenaran tidak hanya terpaku pada persesuaian
tertentu, namun lebih dari itu kebenaran sejati ditandai oleh tercerahkannya hati
manusia terhadap hal-hal yang hakiki.16
Di sinilah lahir kolaborasi teori kebenaran
mulai dari Barat yang materialis, rasionalis hingga Islam yang intuitif. Murtaḍá
mengatakan, pada diri manusia ada sifat kehewanan dan kemanusiaannya.
Karakteristik khas dari kemanusiaannya ialah iman dan ilmu. Manusia mempunyai
13
Murtaḍá Muṭahharī, Epistemologi Islam, h. 216. 14
Murtaḍá Muṭahharī, Epistemologi Islam, h. 217. 15
Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, (Jakarta: Rajagrafindo Press, 2012), h. 118. 16
Murtaḍá Muṭahharī, Manusia dan Alam Semesta ..., h. 54.
72
gerakan menuju ke arah kebenaran-kebenaran dan wujud-wujud suci. Manusia
tidak bisa hidup tanpa menyucikan dan memuja sesuatu.17
Kebenaran intuitif diberikan tempat oleh Murtaḍá Muṭahharī. Ia mengakui
bahwa terdapat kebenaran intuitif sebagaimana yang ditawarkan oleh Ibnu ʻArabī.
Hanya saja, Murtaḍá tidak kemudian menerima sepenuhnya pemikiran Ibnu
ʻArabī. Konsep kebenaran yang ditawarkan oleh Ibnu ʻArabī menurutnya terlalu
ekstrem terhadap kebenaran intuitif hingga meniadakan kebenaran yang lain.
Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan bentuk kritik Murtaḍá terhadap bagian-
bagian tertentu dari teori kebenaran intuitif Ibnu ʻArabī. Di situlah Murtaḍá
menilai bahwa kebenaran yang diusung oleh para sufi yang hanya menerima
kebenaran intuitif tersebut tidak berlandaskan al-Qur‟an.18
Kolaborasi berbagai teori kebenaran tersebut tidak mengejutkan mengingat
Murtaḍá memang fokus pada menanggapi problematika umat Islam yang sedang
bermasalah dan menghadapi dilema, sehingga ia mencoba mengembangkan harga
diri Muslim Iran. Dunia Muslim pada saat itu tidak memiliki ulama terkemuka
yang bisa berintegrasi pemikiran keagamaan dengan pemikiran Barat. Muṭahharī
menerima tantangan melalui pendekatan filosofis.19
Oleh karena itu, Murtaḍá
mencoba untuk merangkul beberapa teori besar Barat dan digabungkan dengan
teori filsafat Islam. Tidak hanya itu, Murtaḍá juga mendamaikan filsafat dan
tasawuf yang awalnya mempunyai perbedaan yang sangat mendasar. Murtaḍá
merupakan seorang filosof yang menurut peneliti ia mengikuti madzhab teosofi
(al-ḥikmat al-muta„ālīyah) Mullā Ṣadrā yang berupaya memadukan metode-
metode wawasan spiritualitas dengan metode-metode deduksi filosofis.20
Pemikiran Murtaḍá merupakan sebuah perpaduan antara filsafat dan tasawuf,
sehingga dalam teori kebenarannya pun merupakan penggabungan antar keduanya.
Bahkan lebih dari itu, Murtaḍá sangat terbuka kepada kebenaran yang
berasal dari filosof-filosof Barat seperti materialisme dengan tetap menyaring hal-
hal yang keliru dari pemikiran mereka. Dengan tegas Murtaḍá mengatakan bahwa
kebenaran bisa didapatkan dari manapun. Ia berargumen bahwa Islam adalah
agama yang realistis. Arti kata Islam ialah tunduk, patuh dan menerima. Ini
menunjukkan bahwa syarat pertama menjadi seorang muslim ialah menerima
realitas dan kebenaran. Islam menolak setiap bentuk keras kepala, taklid buta dan
egoisme. Seorang muslim sejati harus dengan gairah menerima kebenaran dari
manapun kebenaran itu didapatkan. Sejauh menyangkut menuntut ilmu
pengetahuan, seorang muslim tidak memiliki prasangka dan sikapnya tidak berat
17
Murtaḍá Muṭahharī, Bedah Tuntas Fitrah. Mengenal Jati Diri, Hakikat dan
Potensi Kita, (Jakarta : Citra, 2011), h. 15. 18
Mohd Shaiful Ramze Endut, “Ali Shari‟ati and Morteza Motahhari‟s Ideological
Influences on Intellectual Discourse and Activism in Indonesia”, dalam International
Proceedings “Asian Public Intelectuals”, 2009/2010, h. 212. Diakses pada 12 oktober 2019
dari http://www.api-fellowships.org/body/international_ws_proceedings/09/P5-Mohd.pdf 19
Mohd Shaiful Ramze Endut, “Ali Shari‟ati and Morteza Motahhari‟s Ideological
Influences on Intellectual Discourse and Activism in Indonesia”, dalam International
Proceedings “Asian Public Intelectuals”, 2009/2010, h. 208. Diakses pada 12 oktober 2019
dari http://www.api-fellowships.org/body/international_ws_proceedings/09/P5-Mohd.pdf 20
Haidar Bagir, Murtaḍá Muṭahharī Sang Mujahid Sang Mujtahid, h. 34.
73
sebelah. Kebenaran tidak hanya terbatas pada masa tertentu, dan juga tidak hanya
terbatas pada wilayah tertentu atau dari orang tertentu. Nabi menyerukan agar
umat Islam menerima ilmu pengetahuan dari seorang penyembah berhala
sekalipun.21
Maka tidak heran ketika dalam karyanya ia banyak mengutip filosof-
filosof Barat.
2. Persoalan Pembawa Kebenaran
Pembawa kebenaran tidak dapat dilepaskan dari kebenaran itu sendiri,
karena kebenaran didapatkan melalui pembawa kebenaran. Pembawa kebenaran
dalam bahasa Inggris ialah Truth Bearers. Richard mengartikannya sebagai
masalah mencari tahu hal macam apa yang bisa mempunyai nilai kebenaran, yaitu
hal macam apa yang bisa benar atau salah.22
Maka dalam teori kebenaran, tidak
semua hal dapat diuji kebenarannya.
Dalam pandangan Murtaḍá hal-hal yang dapat diuji kebenarannya di
antaranya; pertama ialah persepsi atau rasa.23
Kedua adalah kalimat. Persepsi ia
pahami sebagai gambaran mengenai alam eksternal yang kita dapatkan melalui
indera dan akal. Persepsi menurut Murtaḍá, dapat diuji apakah persepsi tentang
segala sesuatu itu sesuai dengan realitas eksternal atau tidak. Di situlah persepsi
dapat dilacak kebenarannya melalui kesesuaian persepsi dengan kenyataan.
Kalimat menurut Murtaḍá merupakan salah satu yang dapat dicek
kebenarannya, namun terdapat kriteria tertentu agar kalimat dapat dijadikan
sebagai pembawa kebenaran. Kalimat yang dapat diuji kebenaran dan
kekeliruannya ia istilahkan dengan qadhiyah. Qadhiyah adalah Murakkab tām
khabar.24
Untuk memahami definisi dari Murakkab, tām dan khabar sebaiknya
penulis akan membahasnya secara runtun.
Kajian tentang tiga istilah tersebut berawal dari pembahasan tentang Qaul.
Qaul ialah kata yang merujuk kepada suatu arti tertentu. Jadi suatu kata yang
mewakili arti tertentu ia dinamakan qaul. Jika kata tidak merefleksikan apapun,
maka ia dinamakan muhmal. Kata “kucing” adalah qaul, karena ia merujuk kepada
makna tertentu. Kata “lalihu” bukanlah qaul, melainkan muhmal karena ia tak
berarti apapun.25
Muṭahharī kemudian membagi Qaul menjadi 2 bagian, yaitu mufrad dan
Murakkab (kompositif, susunan kata). Mufrad disebut juga dengan istilah kata
tunggal atau singular, sedangkan Murakkab disebut juga kata jamaʻ atau kata yang
tersusun (susunan kata). Jika qaul memiliki beberapa bagian dan masing-masing
21
Murtaḍá Muṭahharī, Manusia dan Alam Semesta ..., h. 60. 22
Richard L. Kirkham, Theories of Truth, (Cambridge: Massachusetts Institute of
Technology Press (MIT Press), 1992), h. 54. 23
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Filsafat Islam: Filsafat Teoritis Dan Filsafat
Praktis. Penerjemah M. Ilyas, (Yogyakarta: Rausyanfikr, 2003), h. 71. 24
Murtaḍá Muṭahharī, Belajar Konsep Logika: Menggali Struktur Berpikir ke Arah
Konsep Filsafat. Penerjemah Ibrahim Husein Al-Habsyi, (Yogyakarta: Rausyanfikr Institute,
2013), h. 43. 25
Murtaḍá Muṭahharī, Belajar Konsep Logika ..., h. 41.
74
menunjukkan bagian tertentu dari arti, disebut Murakkab. Jika tidak menunjukkan
bagian tertentu, maka disebut dengan mufrad.26
Susunan kata yang oleh Muṭahharī disebut sebagai Murakkab terbagi
menjadi tām dan nāqiṣ. Murakkab tām ialah susunan kata yang mencakup dan
menjelaskan maksud dengan sempurna. “Apa pun engkau akan pergi bersamaku?”
Atau contoh “Ilham datang ke sini” adalah contoh dari tām. Sedangkan nāqiṣ tidak
ialah susunan kata yang menunjukkan suatu makna tapi tidak sempurna. Istilah
tidak sempurna dapat kita pahami sebagai susunan kata yang tidak mempunyai
subjek dan predikat. “Air gula” merupakan contoh dari nāqiṣ. Susunan kata “air
gula” merupakan dua kata tanpa diikuti oleh tambahan apapun, sehingga
pendengar akan menunggu tambahan dari pembicara dan akan bertanya kenapa?
Sementara itu, Murakkab naqis terkadang panjang namun tidak menjelaskan
maksud pembicaraan dengan sempurna.27
Murakkab tām dibagi menjadi khabar (deklarasi/proposisi) dan inshak
(komposisi originatif). Murakkab tām khabar ialah susunan kata sempurna yang
menceritakan suatu hakikat tertentu. Bisa dikatakan menjelaskan tentang hal yang
telah sedang akan terjadi selalu ada atau akan selalu ada. Contoh. Saya tahun lalu
telah pergi haji. Saya tahun depan akan mendapat gelar sarjana. Saya sekarang
masih sakit. Air membeku karena turunnya suhu udara. Tām yang insyaf ialah
murakkab yang tidak menceritakan suatu hakikat tertentu, tapi Murakkab tersebut
yang mewujudkan suatu hakikat yang baru. Seperti pergilah engkau. Datanglah
engkau. Akankah engkau bersamaku.28
Murakkab tām khabar –karena menceritakan dan memberikan informasi
mengenai sesuatu– ada kemungkinan berita atau narasi tersebut cocok dengan
yang terjadi, mungkin juga tidak. Seperti ketika kita mengatakan, saya tahun lalu
pergi haji. Bisa jadi memang betul tahun lalu pergi haji dan khabar tersebut
menjadi benar, bisa juga tidak demikian dan khabar tersebut menjadi bohong atau
salah. Adapun Murakkab inshaf karena tidak menceritakan sesuatu melainkan
dengan sendirinya mengadakan suatu hal baru. Tidak memiliki hal, yang cocok
dengannya atau tidak, di alam luar. Dengan demikian bagi insyaf kebenaran atau
kebohongan tidak memiliki arti apapun.29
Penjelasan-penjelasan di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa
kalimat yang bisa diverifikasi kebenarannya disebut sebagai Qadhiyah. Sedangkan
qadhiyah itu sendiri ialah kalimat sempurna dan mempunyai makna atau arti
tertentu yang jika kita verifikasi akan tampak salah dan benarnya. Dengan kata
lain, qadhiyah adalah susunan kata sempurna yang menceritakan suatu kenyataan
di masa lalu, kini dan mendatang dengan kemungkinan benar atau salah.
3. Pandangan Murtaḍá tentang Fakta
Pemahaman terhadap fakta bagi Murtaḍá merupakan hal yang sangat
penting, bahkan pemahaman tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan
26
Murtaḍá Muṭahharī, Belajar Konsep Logika ... h. 42. 27
Murtaḍá Muṭahharī, Belajar Konsep Logika ..., h. 42. 28
Murtaḍá Muṭahharī, Belajar Konsep Logika ..., h. 42. 29
Murtaḍá Muṭahharī, Belajar Konsep Logika ..., h. 43.
75
terhadap benar tidaknya suatu pembawa kebenaran.30
Kebenaran hanya akan
menjadi sebuah impian, manakala pencari kebenaran dalam memahami fakta tidak
tepat. Kekeliruan seperti ini terjadi pada Feuerbach. Feuerbach memahami suatu
agama sebagai produk interaksi sosial, sehingga ia memandang bahwa agama
sebagai produk sosial dan menjauhkannya dari Tuhan.31
Sejak awal Feuerbech telah menjauhkan agama dari ketuhanan, sehingga
wajar ketika ia mengatakan bahwa agama lahir karena keterasingan manusia dari
dirinya. Hal ini seperti kekeliruan tentang angka 13 yang diasumsikan sebagai
fakta yang menyimpan kejadian-kejadian kecelakaan. Padahal menurut Murtaḍá
angka 13 tidak lain adalah sama seperti angka yang lain. Maka asumsi tentang
angka 13 yang menyimpan kajian naas adalah objek yang keliru karena tidak logis.
Jika suatu teori dilandaskan pada objek yang keliru, maka konsep yang
ditawarkannya pun akan keliru.
Menurut Murtaḍá, apa yang disebut sebagai fakta? Murtaḍá mengatakan
bahwa fakta merupakan sesuatu yang dengan dirinya ia bernilai sebagai fakta.
Secara fitrah, ia memang tercipta sebagai sebuah fakta. Pernyataan Murtaḍá ini
disampaikan ketika ia mengkritik konsep fakta eksistensialisme. Eksistensialis
memahami fakta sebagai hal yang dapat diciptakan oleh manusia. Sesuatu yang
abstrak dan metafisik dapat dikatakan sebagai fakta ketika manusia telah
memberikan realitas dan hakikat kepada sesuatu tersebut.32
Seperti halnya
perubahan seseorang ketika telah diberikan realitas baru kepadanya. Manusia akan
berubah menjadi manusia lebih unggul ketika ia telah diberikan realitas yang lebih
unggul.
Murtaḍá menolak apa yang dikatakan oleh eksistensialis. Fakta yang
hakiki menurut Murtaḍá merupakan fakta yang sejak awal ia tercipta sebagai fakta.
Manusia menurutnya akan tetap menjadi sebagai manusia walau diberi tambahan
apapun terhadapnya. Ketika fakta dipahami sebagai sesuatu yang berubah, maka
teori-teori tentang fakta tersebut juga akan mengalami perubahan-perubahan.
Ketika teori terus menerus mengalami perubahan, maka pengujian terhadap
kebenaran suatu teori tidak dapat dilakukan.33
Baginya fakta yang dapat dijadikan objek sebuah pembawa kebenaran
ialah meliputi hal fisik dan nonfisik 34
yang kemudian ia sebut sebagai fakta di luar
dirinya (fakta eksternal atau eksistensi eksternal) dan yang terdapat dalam dirinya
(eksistensi mental). Fakta eksternal merupakan ialah fakta yang terlepas dari
mental manusia. Fakta eksternal merupakan suatu fakta yang meskipun seseorang
tidak memikirkannya, ia akan tetap ada. Di antara fakta fisik ialah bumi, langit,
30
Murtaḍá Muṭahharī, Fitrah: Menyingkap Hakikat, Potensi dan Jati Diri Manusia.
Penerjemah H. Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 153-157. 31
Robert C.Solomon dan Kathleen M.Higgins, Sejarah Filsafat. Penerjemah Saut
Pasaribu, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya), h. 405. Liat juga di L. Feuerbach,
Lectures on the Essence of Religion, Harper and Row, (New York, 1967, h. 22. 32
Murtaḍá Muṭahharī, Fitrah: Menyingkap Hakikat, Potensi dan Jati Diri Manusia.
Penerjemah H. Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 145-150. 33
Murtaḍá Muṭahharī, Epistemologi Islam, h. 219. 34
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Filsafat Islam: Filsafat Teoritis Dan Filsafat
Praktis. Penerjemah M. Ilyas, (Yogyakarta: Rausyanfikr, 2003), h. 21.
76
bintang, matahari, bulan, mendung, binatang dan segala yang ada di sekitar
manusia yang dapat ditangkap oleh indra. Q.S. Yunus ayat 101.35
Fakta internal merupakan fakta yang berada di dalam mental seseorang,
seperti pengetahuan-pengetahuan yang sudah pasti seperti lingkaran, segi empat
dll.36
Murtaḍá mengakui adanya realitas-realitas nonfisik yang tidak dapat
diketahui melalui indra, tetapi ia dapat diketahui melalui unsur lain manusia.37
Murtaḍá juga memaparkan bahwa realitas mental bukan hanya lahir dan berasal
dari mental itu sendiri, melainkan juga bisa merupakan sebuah abstraksi dari
realitas eksternal. Abstraksi tentang gunung yang ada dalam mental kita
merupakan suatu realitas mental dan hakiki, karena ia merupakan suatu esensi dari
benda-benda eksternal dalam mental kita.38
Dari pembagian tentang realitas tersebut, Murtaḍá tampaknya
menyamakan Tuhan dengan benda lain sebagai sama-sama mempunyai realitas.
Tuhan yang transenden dan wujud lainnya mempunyai realitasnya sendiri,
termasuk Tuhan. Murtaḍá kemudian memperjelas maksud dari teorinya dengan
membuat beberapa perbedaan antara realitas selain Tuhan, dengan Tuhan itu
sendiri. Ia mengatakan bahwa yang membedakan dari Tuhan dan yang selainnya
ialah Tuhan adalah wájib al-wujūd dan ada dengan sendirinya, maka benda-benda
lain selain Tuhan hanyalah sebagai ada karena sesuatu yang lain dan merupakan
akibat dari wájib al-wujūd. Tuhan meliputi dan mencakup segala sesuatu. Jadi
segala sesuatu adalah nama, kualitas dan manifestasi dari Tuhan, bukan berada di
samping Tuhan.39
Lebih rinci ia mengklasifikasikan fakta universal terbagi menjadi empat di
antaranya ialah fakta materi (tabi’ah atau nasut), fakta ideal (mithál), fakta rasional
(uṣūl), dan fakta ketuhanan (ulūhiyah). Fakta materi adalah realitas yang berada
dalam ruang dan waktu yakni sesuatu yang dapat ditangkap oleh indra. Fakta ideal
adalah fakta yang lebih tinggi dari fakta materi yang memiliki berbedagai bentuk
dan dimensi, namun tidak memiliki gerak, waktu dan perubahan. Sedangkan fakta
rasional ialah alam makna, yang terlepas dari berbagai bentuk dan bayangan, dan
di atas alam ideal.40
4. Sumber-sumber Kebenaran
Murtaḍá mengakui terdapat tiga sumber yang dapat digunakan untuk
memperoleh pengetahuan yang benar, yaitu indra, akal dan hati. Apa-apa yang
ditangkap oleh 3 hal tersebut, Murtaḍá akui bahwa ia adalah kebenaran. Dalam hal
ini, berbeda dengan beberapa filosof lain yang cenderung hanya menerima apa-apa
yang berasal satu sumber saja dan mencampakkan sesuatu yang berasal dari
35
Murtaḍá Muṭahharī, Manusia dan Alam Semesta: Konsep Islam tentang Jagat
Raya. Penerjemah Ilyas Hasan, (Jakarta: Lentera, 2002), h. 47. 36
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Filsafat Islam ..., h. 69-70. 37
Murtaḍá Muṭahharī, Filsafat Agama dan Kemanusiaan. Penerjemah Arif
Maulawi, (Yogyakarta: Rausyanfikr, 2013), h. 79. 38
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Filsafat Islam: Filsafat Teoritis dan Filsafat
Praktis. Penerjemah M. Ilyas, (Yogyakarta: Rausyanfikr, 2003), h. 70. 39
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Ilmu-ilmu Islam, h. 377. 40
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Filsafat Islam, h. 63.
77
sumber lainnya. Kaum materialisme seperti Karl Marx, menolak akal dan hati
sebagai suatu yang dapat melahirkan kebenaran. Para sufi hanya menerima hati
sebagai sumber satu-satunya yang dapat menemukan kebenaran. Plato yang
merupakan bapak filosof idealisme hanya mengakui akal sebagai instrumen
kebenaran.41
Padahal menurut Murtaḍá semua alat-alat tersebut dapat digunakan
dalam mencapai kebenaran. Alat-alat mempunyai ranah masing-masing yang
antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Di sisi lain Muṭahharī
mengindikasikan superioritas epistemologi Islam yang selain mengakui validitas
indera sebagai instrumen dan sumber pengetahuan, juga mengakui validitas akal
dan hati.
Murtaḍá mengatakan bahwa indra, akal dan hati merupakan suatu alat
yang dapat dipergunakan sebagai untuk mendapatkan kebenaran. Melalui tiga alat
tersebut manusia mendapatkan pengetahuan yang benar.42
Al-Qur‟an tidak pernah
menyatakan alat pengetahuan hanyalah indra dan rasio. Demikian pula tidak
mengatakan bahwa alat pengetahuan itu hanya hati. Karena al-Qur‟an beranggapan
masing-masing alat itu memiliki wilayah yang berbeda. Berbagai wilayah tidak
sama dengan berbagai topik.43
Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Naḥl ayat
78 dan al-„Ankabūt ayat 69 dan al-Shams ayat 1-10, al-Qur‟an mengatakan
manusia mempunyai tiga alat yang dapat digunakan semaksimal mungkin sesuai
dengan ranah kemampuannya. Masing-masing mempunyai kelebihan dan
kekurangan serta antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi.
Demikian pula dengan persepsi akal. Akal mempunyai tempat sendiri
dalam mencapai kebenaran. Ketika akal telah bekerja dengan baik dan sesuai
dengan aturan-aturan berpikir yang telah teruji, maka persepsi yang ia dapatkan
akan benar. Maka argumen rasional kita tersebut dapat kita katakan sebagai
kebenaran. Contohnya ialah ketika kita menjual bolpoin, kita kemudian
mengklasifikasi bolpoin kita berdasarkan bentuknya. Proses pemetaan ini
sebenarnya yang disebut dengan kinerja akal dan pikiran. Ketika proses ini
dikerjakan dengan baik, teliti dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, konsep
akal tersebut dapat dikatakan benar dan sesuai dengan kenyataan44
Indra hanya bisa menjangkau kebenaran-kebenaran yang bersifat fisik
yang terbatasi oleh ruang dan waktu. Akal bisa menjangkau apa yang bersifat
rasional seperti klasifikasi, silogisme, demonstrasi dan berbagai argumen logika
lainnya. Sedangkan hati merupakan alat untuk menjangkau kebenaran yang
bersifat intuitif seperti ilham, wahyu, hikmah, Tuhan, dan hal-hal lain yang berada
di balik alam materi.45
Murtaḍá mengibarat beberapa alat tersebut bagaikan cermin. Cermin
menangkap hal-hal yang ada di hadapannya manakala cermin tersebut dalam
41
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Filsafat Islam ..., h. 54. 42
Murtaḍá Muṭahharī, Epistemologi Islam ..., h. 55-54. 43
Murtaḍá Muṭahharī, Falsafath Kenabian. Penerjemah Ahsin Muhahham, (Jakarta:
Pustaka Hidayah. 1991), h. 94. 44
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Filsafat Islam: Filsafat Teoritis Dan Filsafat
Praktis. Penerjemah M. Ilyas, (Yogyakarta: Rausyanfikr, 2003), h. 72. 45
Murtaḍá Muṭahharī, Epistemologi Islam, h. 77-79.
78
kondisi yang baik dan bersih. Ketika cermin tersebut rusak dan kotor, maka ia
tidak dapat menangkap objek sebagai mana mestinya.46
Pada saat itu pula alat-alat
ini tidak akan pernah sampai pada kebenaran. Panca indra tidak akan pernah
mampu menangkap objek dengan baik ketika ia rusak atau terdapat sesuatu yang
menghalanginya. Begitu pula ketika hati dan akal kotor maka ia pun tidak akan
mampu mencapai kebenaran. Lebih detailnya, penulis jelaskan pada pembahasan
berikutnya.
B. Berbagai Model Kebenaran dan Ruang Lingkupnya
1. Kebenaran Meteri
Kebenaran materi merupakan kebenaran yang penentu kebenarannya
berada pada objek yang bersifat materi.47
Kebenaran ini juga dapat dikatakan
sebagai kebenaran empiris di mana kebenaran ditentukan oleh pengalaman-
pengalaman langsung terhadap realitas yang bersifat materi. Murtaḍá Muṭahharī
mengakui teori ini, meskipun ada beberapa pemikiran penganutnya ia tolak.
Kebenaran ini oleh Murtaḍá dikatakan sebagai kebenaran seperti kebenaran
lainnya.
Meskipun tidak sedikit pemikir Islam yang menolak sepenuhnya dari
kebenaran materi ini, namun menurut Murtaḍá kebenaran yang berpangkal pada
indra tersebut dapat diterima kebenarannya. Baginya indra mempunyai peran
tersendiri dalam menentukan kebenaran. Ia menjelaskan bahwa persepsi indra
banyak yang dapat kita katakan sebagai kebenaran yang nyata.48
Hal-hal yang
bersifat indrawi merupakan bagian dari kenyataan yang tak dapat kita pungkiri.
Siang dan malam merupakan suatu fakta, dan persepsi tentangnya dapat kita
verifikasi kebenarannya.
Ketika seseorang dalam persepsinya mengatakan siang telah tiba, dan
ketika kita keluar rumah ternyata keadaan memang siang, maka persepsi indrawi
tersebut adalah kebenaran. Pada titik ini sebenarnya tidak ada yang dapat
membantah keberadaan kebenaran materi, karena kebenarannya dapat dirasakan
secara langsung oleh manusia.49
Teori kebenaran materi ini merupakan teori yang
bersifat sederhana, karena kebenaran ini berasal dari interaksi langsung antara
indra dengan objek, maka tidak ada keraguan ataupun sanggahan.50
Kebenaran materi memang tidak dapat dipungkiri. Kebenaran itu adalah
nyata dan ada, namun kebenaran yang berbasis pada materi mempunyai batasan-
batasan tertentu. Kebenaran materi mempunyai ruang lingkup hanya pada hal-hal
46
Murtaḍá Muṭahharī, Epistemologi Islam, h. 165-166. 47
Adanya kebenaran selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia mengenai
objek. Jadi, kebenaran itu ada pada sejauh mana subjek mempunyai pengetahuan mengenai
objek. Sedangkan pengetahuan berasal mula dari banyak sumber. Sumber-sumber itu
kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Suparlan Suhartono, Filsafat Ilmu
Pengetahuan: Persoalan Eksistensi dan Hakikat Ilmu Pengetahuan, (JogJakarta: Ar Ruzz
Media, 2005), h. 82. 48
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Filsafat Islam: Filsafat Teoritis Dan Filsafat
Praktis. Penerjemah M. Ilyas, (Yogyakarta: Rausyanfikr, 2003), h. 72. 49
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Epistemologi Islam, h. 142. 50
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Epistemologi Islam, h. 142.
79
yang bersifat materi, meskipun jangkauannya juga terbatas. Seperti halnya
telinga yang hanya mampu menangkap frekuensi suara dengan kecepatan 16000-
32000/detik.51
Gelombang di luar itu tidak dapat ditangkap oleh telinga meskipun
gelombang tersebut ada. Jika dalam menangkap realitas materi saja pancaindra
masih terbatas, apalagi untuk menangkap realitas metafisik, maka itu tidak
mungkin dilakukan. Oleh karena itu, menggunakan kebenaran materi sebagai
standar kebenaran immateri adalah keputusan yang tidak tepat, bahkan ia akan
menyesatkan.
Pada kenyataannya manusia telah mengakui kebenaran nonmateri seperti
kebenaran metafisik. Pengetahuan empiris ini tidak dapat menjangkau kebenaran
yang bersifat metafisik.52
Kebenaran yang basis materi hanyalah sebagian dari
keseluruhan kebenaran. Murtaḍá mengibaratkannya dengan pandangan tentang
gajah, kebenaran materi seperti hanya menangkap kebenaran tentang telinga
gajah. Jadi kebenaran yang ia dapatkan tentang gajah hanyalah sebagian dari
kebenaran tentang gajah secara keseluruhan. Kebenaran materi hanyalah bersifat
khusus atau partikular. Wajar ketika kebenaran materi selalu berubah-ubah atau
direvisi oleh teori-teori yang lebih baru yang mampu meruntuhkan teori
sebelumnya.
Objek kebenaran fisik terus menerus berubah-ubah setiap saat. Segala
sesuatu yang ada di alam ini tidak tetap. Ia selalu berbeda dalam dua kesempatan
berbeda. Maka kebenaran materi akan juga selalu berubah sesuai dengan
perubahan objeknya.53
Kerap kita menemukan teori ilmiah selalu direvisi oleh
teori ilmiah lain yang lebih baru, hal itu terjadi karena materi selalu berubah,
sehingga kebenarannya pun akan selalu berubah.
Namun pada kesempatan berikutnya, Murtaḍá kemudian melanjutkan,
sesungguhnya perubahan hukum lama kepada yang baru bukanlah tanda bahwa
hukum yang lama itu keliru, namun hukum tersebut berganti kepada hukum baru
yang berbeda. Perbedaan itu disebabkan oleh perubahan objek syarat-syarat yang
tersedia. Jadi hukum yang lama benar sesuai dengan keadaan ketika penelitian,
kemudian hukum yang kedua benar sesuai dengan keadaan yang terbaru. Dua
hukum tersebut tidak saling menafikan, tetapi secara materi objeknya telah
berubah.54
Kebenaran materi sesungguhnya terikat dalam kerangka sejumlah
syarat tertentu dan terbatas, sehingga teori yang sama belum tentu bisa diterapkan
kepada objek yang sama dalam waktu dan keadaan yang berbeda, karena objek
tersebut juga telah ikut berubah sesuai perubahan waktu dan keadaan.
51
Murtaḍá Muṭahharī, Filsafat Moral Islam: Kritik atas Berbagai Pandangan
Moral. Penerjemah Muhammad Babul Ulum dan Edi Hendri M, (Jakarta: al-Huda, 2004), h.
159. 52
Murtaḍá Muṭahharī, Manusia dan Alam Semesta: Konsep Islam Tentang Jagat
Raya. Penerjemah Ilyas Hasan, (Jakarta: Lentera, 2002), h. 51. 53
Murtaḍá Muṭahharī, Filsafat Moral Islam: Kritik atas Berbagai Pandangan
Moral. Penerjemah Muhammad Babul Ulum dan Edi Hendri M, (Jakarta: al-Huda, 2004), h.
158. 54
Murtaḍá Muṭahharī, Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam. Penerjemah
Muhammad Abdul Mun‟im al-Khaqani, (Bandung: Mizan, 2009), h. 129.
80
Ruang lingkup kebenaran materi bisanya tertuju kepada objek yang
bersifat materi. Di mana pembawa kebenarannya merujuk kepada apa-apa yang
bersifat materi di antaranya ialah bersifat partikular atau satu persatu, bersifat
lahiriah atau materialis, bersifat sekarang dan berhubungan dengan kawasan atau
lingkungan tertentu.55
Berdasarkan objek yang menjadi tolok ukur kebenaran ini,
ciri-cirinya ialah bersifat terbatas, berubah-ubah, ditentukan, bergantung dan
relatif.56
Menurut Murtaḍá ruang lingkup jangkauan kebenaran materi ialah
terbatasi oleh partikel-partikel kecil hingga besar, ruang dan waktu. Di luar
jangkauan tersebut, kebenaran materi tidak mampu merabanya. Kebenaran materi
juga mengalami perubahan-perubahan sesuai situasi dan kondisi. Kita tahu
bahwa objek materi terus berubah, pada saat itu pula kebenaran tentangnya terus
juga berubah dan bersifat partikular.
2. Kebenaran Logis
Sebagaimana telah dijelaskan sepintas pada kesempatan sebelumnya
bahwa kebenaran logis merupakan suatu kebenaran yang diukur oleh sejauh
mana pembawa kebenaran koheren dengan berbagai teori lain yang
kebenarannya sudah diverifikasi. Murtaḍá memasukkan kebenaran ini sebagai
bentuk kebenaran hakiki, karena kebenarannya tidak dapat diragukan. Ia
menguatkan pendapatnya dengan mengungkap suatu penemuan tentang planet
Neptune yang pada mulanya ditemukan melalui akal. Planet Neptune merupakan
sebuah planet yang ditemukan berdasarkan analisa akal yang dilakukan oleh ahli
matematika dan astronomi tatkala memperhatikan berbagai sistem tata surya. Ia
mengatakan “pada bagian angkasa, mesti ada suatu garis orbit yang lain, dan ada
sebuah planet yang melintas garis orbit itu, dan mustahil sistem tata surya ini
hanya berdiri dari planet ini saja. Jadi planet Neptune pertama kali ditemukan
dari analisa akal. Terbukti setelah ditemukan teleskop planet Neptune tersebut
memang ada, itu berarti kebenaran logis juga dapat dipertanggung jawabkan.57
Dalam kasus ini, antara kebenaran logis dengan kebenaran empiris bertemu pada
satu titik, yaitu kebenaran hakiki.
Meskipun kebenaran ini digolongkan kebenaran hakiki, kemungkinan
kekeliruan tetap masih ada jika terdapat hal-hal yang bisa mengakibatkan ia
keliru. Akal sebagai alat yang mampu menalar dan menemukan kebenaran dapat
mencapai kebenaran jika akal memiliki lebih dari satu informasi58
(konsep) yang
oleh Murtaḍá disebut sebagai maklum. Selanjutnya ialah adanya penghubung di
antara maklum-maklum tersebut.
Teori kebenaran logis ini pada dasarnya tidak berkaitan dengan realitas
materi. Ia hanya bertumpu kepada teori-teori abstrak, namun ada kalanya teori
yang abstrak tersebut berkaitan dengan fakta materi seperti pada teori yang
dilahirkan dari deduksi yang ditemukan melalui eksperimen. Pada keadaan ini,
maka kebenaran logis secara otomatis berkaitan dengan materi. Misalnya teori
tentang sebab dari suatu akibat. Menurut Murtaḍá, sejauh ia menyangkut dimensi
55
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Epistemologi Islam, h. 127-129. 56
Murtaḍá Muṭahharī, Manusia dan Alam Semesta ..., h. 60-64. 57
Murtaḍá Muṭahharī , Pengantar Epistemologi Islam, h. 208. 58
Informasi ini bisa didapatkan melalui berpikir atau melalui pancaindra.
81
material dunia ini, sistem sebab-akibat bersifat material, namun sejauh
menyangkut dimensi spiritual dunia ini, sistem sebab akibatnya bersifat
nonmateri. Ketika suatu proposisi berkaitan dengan materi di mana ia merupakan
suatu abstraksi dari realitas materi, maka pada waktu itu pula kebenaran logis
berkaitan dengan materi. Namun, kemudian ia menegaskan bahwa antara dua
sistem tersebut tidak bertentangan. Masing-masing sistem ada tempatnya
sendiri.59
Hal ini tidak lepas dari prinsip logika Murtaḍá dalam mengkaji tentang
proposisi. Ia menjelaskan bahwa dalam logika proposisi dibagi menjadi dua yaitu
proposisi afirmatif dan proposisi negatif. Dalam proposisi afirmatif, keputusan
pikiran kita pastilah jelas, baik kita membenarkan dan mengonfirmasikan
eksistensi subjek dalam proposisi maupun melekatkan predikat dan sifat tertentu
padanya. Misalkan Mahmud sedang berdiri. Proposisi afirmatif terdapat
keputusan dan penegasan akal tentang adanya hubungan objektif antara subjek
dan predikat. Sedangkan dalam proposisi negatif, ke-ada-an hubungan luar itu
ditolak oleh akal. Oleh karena itu, inti proposisi negatif bukan menyatakan
adanya “hubungan tiada” antara subjek dan predikat di alam luar. Sebaliknya,
proposisi negatif bertujuan untuk menegaskan bahwa hubungan antara afirmasi
antara subjek dan predikat yang ada dalam bentuk konseptual dalam benak kita
tidak terwujud di alam luar.
Dengan kata lain, apa yang ditegaskan dan dibenarkan dalam proposisi
afirmatif ialah penjelmaan hubungan subjek dan predikat dalam realitas
eksternal. Sementara dalam proposisi negatif apa yang ditegaskan adalah
ketiadaan atau tidak terjadinya hubungan tersebut. Proposisi afirmatif bermaksud
menegaskan korespondensi hubungan subjek predikat dalam proposisi dengan
realitas eksternal, sementara proposisi negatif menegaskan ketiadaan
korespondensi semacam ini. Sehingga contoh Mahmud tidak berdiri bukan
merupakan proposisi negatif dari proposisi Mahmud sedang berdiri, melainkan
proposisi afirmatif. Hal itu disebabkan karena Mahmud tidak berdiri merupakan
bentuk afirmasi atau penegasan atas ketidak berdirian Mahmud. Jadi bukan
menafikan proposisi yang awal. Bentuk proposisi negatif dari Mahmud sedang
berdiri ialah tidak benar Mahmud sedang berdiri. Yang proposisi tersebut
kemudian dapat dipahami bahwa di dunia Mahmud berdiri tidak terwujud dalam
dunia eksternal.60
Jadi proposisi negatif ialah suatu proposisi yang menafikan
seluruh kandungan proposisi afirmasi.
3. Kebenaran Intuitif
Irfan merupakan istilah yang sering kita temukan dalam pembahasan
tentang pengetahuan intuitif di kalangan pemikir syiah.61
Demikian juga Murtaḍá
dalam membahas tentang pengetahuan intuitif ia cenderung kepada pengetahuan
intuitif. Baginya pengetahuan intuitif merupakan pengetahuan yang digapai
59
Murtaḍá Muṭahharī, Manusia dan Alam Semesta, h. 188. 60
Murtaḍá Muṭahharī, Filsafat Hikmah. Penerjemah Tim Penerjemah Mizan,
(Bandung: Mizan, 2002), h. 141-143. 61
Sabara, “Pemikiran Tasawuf Murtaḍá: Relasi Dan Kesatuan Antara
Intelektualitas, Spiritualitas dan Moralitas”, dalam al-Fikr, vol. 20, no. 1, 2016, h. 151.
82
melalui pengalaman dan kesaksian langsung. Murtaḍá kemudian menyamakan
pengetahuan ini dengan ilmu hasil eksperimen di laboratorium, yaitu sama-sama
dapat dialami secara langsung.62
Perbedaannya ialah kalau pengetahuan intuitif
bersifat metafisik, sedangkan pengetahuan empiris bersifat materialis. Kemudian
Murtaḍá meneruskan dalam halaman yang sama bahwa seorang yang meniti jalan
irfan mencari kepastian dan kebenaran pandangan secara langsung.63
Dari apa yang telah disampaikan itu, kita dapatkan bahwa kebenaran
intuitif merupakan suatu pengetahuan sebagaimana adanya tentang suatu realitas
yang didapatkan dari pengalaman langsung melalui perjalanan batin. Dalam
perjalanan spiritual, seseorang akan sampai pada tahap di mana seseorang akan
mampu melihat berbagai hal yang bersifat metafisik. Pada saat itulah, kebenaran
metafisik akan tersingkap kepadanya.64
Murtaḍá ingin menjelaskan pula bahwa
sesungguhnya terdapat objek metafisik yang tak terjangkau oleh indra dan akal.
Objek tersebut hanya ditangkap oleh hati setelah menempuh jalan spiritual.
Kebenaran ini oleh Murtaḍá kemudian dianalogikan dengan kebenaran
materi, di mana kebenaran materi didapatkan ketika pembawa kebenaran telah
dibuktikan secara langsung. Dalam kajian kebenaran intuitif pun demikian, suatu
kebenaran hanya dapat didapatkan jika seseorang mengalami secara langsung,
namun yang membedakannya ialah alat dan objeknya berbeda. Kebenaran materi
ditangkap melalui indra karena objeknya bersifat materi, sedangkan kebenaran
intuitif dicapai menggunakan hati, karena objeknya berupa realitas nonfisik.65
Dalam hal ini, Murtaḍá sepertinya menyamakan status kebenaran intuitif dengan
kebenaran materi sebagai kebenaran yang seharusnya sama-sama diterima.
Menerima kebenaran intuitif ini sebenarnya tidak kemudian
menghilangkan peran akal. Dalam teori kebenaran intuitif, Murtaḍá memandang
bahwa akal justru dihidupkan, sebagai salah satu pendorong terjadinya penyucian
hati.66
Baginya kebenaran intuitif ini tidak hanya berkaitan murni dengan hati,
akan tetapi juga disertai oleh partisipasi akal melalui argumentasi dan penalaran.
Akan tetapi porsi hati lebih banyak dari pada akal.67
Pemahaman ini kemudian
diperkuat oleh hasil penelitian Jamaluddin Rahmat yang mengatakan bahwa
meskipun Murtaḍá mengakui bahwa terdapat kebenaran yang bisa dicapai oleh
hati melalui jalan spiritual, akan tetapi ia menolak adanya teori yang hanya
mengakui kebenaran intuitif. Bahkan Murtaḍá mengatakan tidak ada pencerahan
rohani yang sejati bila tidak dapat diuji secara akliah. Jadi keterkaitan kebenaran
yang satu dengan yang lainnya sangat penting untuk benar-benar memastikan
62
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Ilmu-ilmu Islam, h. 419. 63
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Ilmu-ilmu Islam, h. 419. 64
Murtaḍá Muṭahharī, Filsafat Moral Islam: Kritik atas Berbagai Pandangan
Moral. Penerjemah Muhammad Babul Ulum dan Edi Hendri M, (Jakarta: al-Huda, 2004), h.
157-158. 65
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Ilmu-ilmu Islam, h. 378. 66
Murtaḍá Muṭahharī, Epistemologi Islam, h. 92. 67
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Filsafat Islam, h. 54.
83
kebenaran teori tersebut. Akal baginya tidak menghalangi pencapaian kebenaran
intuitif, justru sangat membantu hati dalam menemukan kebenaran hakiki.68
Namun, menurut penulis peran akal dalam pencapaian kebenaran intuitif
tidak masuk pada inti, akan tetapi akal hanya berperan dalam penyampaian
kebenaran setelah hati telah menemukannya dalam pengalaman mistik.69
Akal
berfungsi sebagai suatu alat yang merasionalisasikan hasil pengalaman mistik
agar juga dapat dipahami oleh akal dan dapat diterima oleh orang lain. Itu berarti
peran akal terhadap kebenaran intuitif berada di luar kebenaran intuitif, tetapi ia
hanya sebagai pelengkap dan media agar kebenaran yang sudah didapatkan
melalui pengalaman langsung, dapat dipahami oleh yang lain.
C. Metode Pembuktian Kebenaran
1. Metode Eksperimen.
Salah satu cara untuk mendapatkan kebenaran menurut Murtaḍá ialah
dengan cara observasi atau eksperimen terhadap berbagai fakta yang terkandung
dalam pembawa kebenaran. Metode observasi merupakan suatu upaya
mencocokkan antara pembawa kebenaran dengan fakta berupa materi. Metode ini
berasal dari keyakinan bahwa manusia dilahirkan dalam kondisi tidak mengetahui
apapun. Bayi yang dilahirkan seperti kertas putih yang tanpa ada satu pun
goresan.70
Kemudian menangkap pengetahuan dari realitas eksternal. Karena
pengetahuan manusia berasal dari realitas eksternal, maka untuk membuktikan
kebenarannya ialah dengan cara mencocokkan pengetahuan tersebut dengan
realitas berupa mengalami langsung atau melakukan eksperimen terhadap objek-
objek yang berkaitan dengan pengetahuan.
Untuk memperkuat pernyataannya, Murtaḍá kemudian menyuguhkan
contoh pembuktian tentang penggerak kehidupan masyarakat. Ketika seseorang
ingin membuktikan penggerak kehidupan masyarakat, maka sebaiknya disaksikan
secara langsung dengan cara hadir dan merasuk di tengah masyarakat. Di situlah
menurut Murtaḍá kebenaran akan siapa yang menggerakkan roda kehidupan
masyarakat ialah elemen-elemen yang tak pernah diduga sebelumnya.71
Di sinilah
sebenarnya tampak bahwa Murtaḍá mengungkap kebenaran dengan cara melihat
objek secara langsung melalui pengalaman empiris berupa melebur bersama
masyarakat.
68
Murtaḍá Muṭahharī, Manusia Sempurna: Pandangan Islam Tentang Hakikat
Manusia. Penerjemah M. Hashem, (Jakarta: Lentera, 2001), h. 13-12. 69
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Ilmu-ilmu Islam, h. 377. 70
Murtaḍá mendadak menjadi seorang materialisme seakan menentang para idealis
seperti Plato dan lainnya. Penyataan ini tidak hanya disebut satu kali, penulis menemukan
bahwa Murtaḍá mengatakan “manusia terlahir dalam kondisi tidak mengetahui apapun”
sebanyak dua kali. Pertama di buku “Pengantar Epistemologi Islam” dan buku “Fitrah” dan
menambahkan argumen dengan mendasarkan kepada an-Nahl ayat 78. Murtaḍá Muṭahharī,
Pengantar Epistemologi Islam, h. 72. Lihat juga di buku Fitrah: Menyingkap Hakikat,
Potensi dan Jati Diri Manusia, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 45. 71
Murtaḍá, Neraca Kebenaran Dan Kebatilan: Menjelajah Alam Pikiran Islam.
Penerjemah Najib Husain Alydrus, (Bogor: IPABI, 2001), h. 53.
84
Kebenaran yang bersifat materi dapat dicapai dengan metode eksperimen
dan cara mengukur kebenarannya pun dengan cara percobaan praktis.72
Dalam
buku “Pengantar Epistemologi Islam”, ia memperinci dalam sebuah contoh
pembuktian kebenaran sederhana. Untuk mengecek kebenaran pembawa
kebenaran “saya melihat meja di ruang sidang”, maka menggunakan cara
menyaksikan secara langsung meja tersebut di ruang sidang. Pembawa kebenaran
itu akan benar manakala di ruang sidang benar-benar ada kursi yang dimaksud.73
Metode ini hanya berlaku untuk menguji kebenaran pembawa kebenaran yang
berkaitan dengan fakta materi yang dapat dirasakan oleh pancaindra. Namun,
jangkauan metode ini sangat terbatas, bahkan dalam membuktikan kebenaran
tentang virus, indra masih membutuhkan alat seperti mikroskop.74
Itu adalah bukti
keberbatasan jangkauan metode ini. Karena untuk membuktikan hal-hal yang
bersifat materi saja terbatas, maka metode ini tidak dapat digunakan pada hal-hal
yang sama sekali tidak mempunyai objek materi seperti hal-hal rasional.
Terdapat kasus-kasus pengetahuan yang objeknya bersifat materi, namun
objek-objek tersebut sudah musnah atau tidak mungkin untuk mencapainya.
Contohnya ialah pengetahuan tentang keberadaan Napoleon pada beberapa abad
silam. Objek-objek dari pengetahuan tentang keberadaan Napoleon sudah musnah
ditelan masa, sehingga untuk mengalami langsung mengenai keberadaannya
adalah hal yang mustahil. Maka untuk mengecek kebenarannya bukan dengan
pembuktian materi, karena ia telah musnah dan tidak mungkin dialami oleh indra.
Hal yang bisa dilakukan ialah membuktikannya menggunakan argumen qiyas
rasional yang dilandaskan pada bukti-bukti peninggalan yang mendukung.75
Pengetahuan tentang keberadaan Napoleon tersebut tidak didasarkan pada
observasi atau eksperimen, melainkan berdasarkan tanda-tanda atau petunjuk yang
didapatkan berupa peninggalan-peninggalan sejarah dan lainnya. Ketika fakta-
fakta materinya sudah tidak lengkap bahkan sudah musnah maka untuk mencapai
kebenaran dari kasus tersebut ialah dengan cara rasional berupa argumen-argumen
qiyas.
Teori ini tampak jelas bahwa Murtaḍá terpengaruh oleh teori kebenaran
yang digagas oleh Bertrand Russell. Namun kemudian Murtaḍá memanfaatkan
teori kebenaran itu untuk mempertahankan teori tentang keberadaan Tuhan. Bahwa
dalam rangka memahami dan mengetahui tentang keberadaan Tuhan, seseorang
tidak perlu mengetahui langsung tentang Tuhan, namun bisa dengan
mengetahuinya melalui tanda-tanda seperti yang telah dikatakan oleh Bertrand
Russell. Ketika kita mengingkari pengetahuan yang dihasilkan melalui tanda
tersebut, maka sebenarnya kita telah mengingkari kebenaran yang telah terbukti
72
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Filsafat Islam: Filsafat Teoritis Dan Filsafat
Praktis. Penerjemah M. Ilyas, (Yogyakarta: Rausyanfikr, 2003), h. 130. 73
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Epistemologi Islam, h. 142. 74
Kadek Agus Kamiana dkk, “Pengembangan Augmented Reality Book Sebagai
Media Pembelajaran Virus Berbasis Android”, dalam Karmapati, vol. 8, no. 2, 2019, h. 165. 75
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Epistemologi Islam, h. 131.
85
ribuan tahun dan manusia akan kehilangan sekitar 90% dari total pengetahuan
manusia.76
2. Metode Koherensi
Murtaḍá tidak hanya mengandalkan eksperimen sebagai satu-satunya
neraca bagi kebenaran. Lebih dari itu, ia juga mengamini teori Aristoteles yang
menjabarkan tentang ilmu atau teori-teori yang sudah diterima sebelumnya sebagai
bagian dari neraca kebenaran.77
Ilmu pengetahuan bagi Murtaḍá dapat dijadikan
sebagai tolok ukur kebenaran. Suatu pengetahuan dapat kita katakan benar
manakala setelah kita teliti terdapat koherensi antara teori tersebut dengan teori-
teori atau ilmu-ilmu yang sebelumnya sudah diakui kebenarannya. Ia berargumen
bahwa suatu teori dapat diukur oleh suatu ilmu, ilmu yang dijadikan sebagai neraca
akan butuh kepada neraca lain yang juga berupa ilmu hingga sampai pada keadaan
di mana ilmu tersebut tidak dapat dijadikan suatu neraca lagi.
Inilah yang disebut dengan metode koherensi dalam mencapai kebenaran.
Metode ini biasanya digunakan untuk mengetahui kebenaran pembawa kebenaran
yang berkaitan dengan realitas mental. Misalkan saja dalam membuktikan teori
sebab dari sebuah akibat. Kita dapat membuktikannya melalui argumen teoritis
yang validitasnya tentang sebab tersebut sudah teruji. Karena menurut Murtaḍá,
akibat bukan selalu berupa sebab dan akibat materi. Sejauh menyangkut dimensi
material dunia ini, sistem sebab akibat bersifat material, namun sejauh menyangkut
dimensi spiritual dunia ini, sistem sebab akibatnya bersifat nonmateri. Antara dua
sistem tidak bertentangan. Masing-masing sistem ada tempatnya sendiri.78
Ketika Murtaḍá menanggapi penyataan yang beredar tentang kemajuan
peradaban Barat yang dianggap sebagai bukti kebenaran teori-teori Barat, Murtaḍá
membuktikannya dengan teori koherensi. Muṭahharī menolak anggapan tersebut,
baginya kemajuan peradaban Barat bukanlah bukti validitas kebenaran ajaran
filsafat Barat. Dengan meminjam logika Bertrand Russell, Muṭahharī menjelaskan
bahwa pengetahuan yang benar akan berujung pada eksperimen yang benar pula,
namun bukan berarti bila eksperimennya benar maka pengetahuannya juga pasti
benar. Inilah yang dinamakan dengan logika lazim ‟am (keterkaitan yang lebih
universal). Memperjelas pernyataan di atas perhatikan keempat pernyataan di
bawah79
:
a. Jika bola maka bulat. Ini adalah pernyataan yang benar. Semua bola mesti
bentuknya bulat. Jika bulat maka bola. Ini adalah pernyataan yang salah.
Tidak semua yang berbentuk bulat itu adalah bola.
b. Jika bukan bola maka tidak bulat. Pernyataan ini juga salah. Jika tidak bulat
maka bukan bola. Pernyataan ini benar. Argumentasi Muṭahharī selanjutnya
menegaskan bahwa filsafat yang benar (hakikat) akan menghasilkan
peradaban yang unggul, adalah pernyataan yang benar sama seperti
pernyataan satu. Pernyataan yang mengatakan bahwa, peradaban yang unggul
76
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Epistemologi Islam, h. 136-137. 77
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Epistemologi Islam, h. 217. 78
Murtaḍá Muṭahharī, Manusia dan Alam Semesta, h. 188. 79
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Epistemologi Islam, (Jakarta: Shadra Press,
2010), h. 272-273.
86
sebagai bukti kebenaran filsafat yang melandasinya, ini adalah pernyataan
yang salah sama seperti pernyataan nomor dua di atas.
3. Metode Pengalaman Batin
Dalam kajian kebenaran logis, kebenaran dari hal-hal yang bersifat
matematis dan hal-hal yang menggunakan argumen deduktif (qiyasi) diperoleh dan
diukur menggunakan melalui logika formal.80
Sedangkan cara yang paling baik
untuk menemukan kebenaran dalam kajian irfan ialah dengan cara mengalami
langsung yaitu melakukan perjalanan mendekati kebenaran hakiki.81
Namun, untuk
mencapai itu tidak mudah, seseorang harus menyiapkan berbagai perangkat berupa
pembersihan dan penyucian jiwa.82
Adapun prosesnya ialah diawali oleh irādah. Irādah berarti kehendak dan
kemauan. Makna lain darinya ialah merupakan munculnya suatu hasrat dan
keinginan kuat serta ingin berpegang teguh pada jalan yang membimbing menuju
kebenaran serta menstimulasi jiwa untuk mencapai tujuannya yang hakiki. Ada
pun hasrat dan keinginan ini bisa dilahirkan melalui argumen atau keimanan.83
Kemudian ia melanjutkan dengan mengutip ʻAbdurrazzāq al-Khasyānī,
menurutnya irādah merupakan gejolak api cinta. Manakala api telah disulut ke
dalam kalbu, manusia pun mulai menanggapi seruan kebenaran. bahkan irādah
kemudian ia pahami sebagai suatu tanggapan terhadap seruan kebenaran atas
kemauan dan kehendak sendiri.84
Ibnu Sīnā mendefinisikan irādah sebagai
kerinduan yang dirasakan manusia tatkala mendapati dirinya kesepian dan tak
berdaya serta ingin bersatu dengan kebenaran sehingga dia tidak lagi merasa
kesepian dan tak berdaya.85
Tahap berikutnya ialah riyāḍah (kehendak dan kemauan). Riyāḍah dalam
kebenaran intuisi dipahami sebagai latihan spiritual dalam rangka menyingkirkan
segala sesuatu selain Allah yang menghalang-halangi di jalan spiritual. Kemudian
menundukkan jiwa yang menyuruh berbuat kejahatan kepada jiwa yang tenang.
Serta melembutkan jiwa batiniah dengan tujuan membuatnya siap menerima
pencerahan.86
Ada pun di antara tahapnya ialah yaqḍoh (kesadaran), taubah
(bertaubat), tafakkur (merenung dan berpikir) serta muhasabah (introspeksi diri).87
Setelah tahapan-tahapan tersebut sudah dilalui dengan baik, sesungguhnya ia telah
melakukan sebuah perjalanan spiritual.
Di antara perjalanan spiritual yang dimaksud Murtaḍá ialah perjalanan dari
makhluk menuju Tuhan. Perjalanan bersama Tuhan dalam Tuhan. Perjalanan dari
Tuhan menuju makhluk dan perjalanan dalam makhluk bersama Tuhan. Dalam
80
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Filsafat Islam: Filsafat Teoritis dan Filsafat
Praktis. Penerjemah M. Ilyas, (Yogyakarta: Rausyanfikr, 2003), h. 130. 81
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Ilmu-ilmu Islam, h. 419. 82
Murtaḍá Muṭahharī, Filsafat Hikmah, h. 113. 83
Murtaḍá Muṭahharī dan Ṭabáṭabáī, Menapak Jalan Spiritual. Penerjemah M.S
Nasrullah, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 66. 84
Murtaḍá Muṭahharī dan Ṭabáṭabáī, Menapak Jalan Spiritual, h. 67. 85
Murtaḍá Muṭahharī dan Ṭabáṭabáī, Menapak Jalan Spiritual, h. 68. 86
Murtaḍá Muṭahharī dan Ṭabáṭabáī, Menapak Jalan Spiritual, h. 68. 87
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Epistemologi Islam, h. 110.
87
perjalanan kedua, sang arif mengenal dan mengetahui nama-nama dan sifat Allah,
dan dia sendiri pun dinapasi oleh sifat-sifat ini. Dalam perjalanan ketika, dia
kembali ke makhluk guna membimbing mereka, tetapi tidak terpisah dari Allah.
Dalam perjalanan keempat, dia melakukan perjalanan di tengah-tengah orang
banyak, tetapi disertai Allah. Dalam perjalanan ini, sang arif tetap bersama orang
banyak serta membantu mereka untuk mendekati dan menghampiri Allah.88
D. Kebenaran dan Fitrah Manusia
1. Hubungan Kebenaran dengan Kesucian Jiwa
Kesucian jiwa merupakan hal yang sangat penting bagi Murtaḍá dalam
kaitannya dengan teori kebenaran. Hati menurutnya mampu mempengaruhi
berbagai unsur dalam diri manusia seperti akal. Jiwa berpengaruh terhadap
kejernihan akal. Semakin suci jiwa seseorang, maka akal seseorang akan semakin
terang.89
Jiwa dan akal mempunyai keterkaitan yang cukup erat hingga mampu
menentukan kecerahan akal. Jiwa bagaikan lampu dalam ruangan yang berfungsi
memberikan cahaya bagi objek agar akal mampu menangkap objek dengan benar.
Ketika lampu ruangan hidup, maka akal dapat menangkap objek sebagaimana
adanya, namun bila gelap maka akal tak akan bisa menangkap objek dengan benar.
Pada keadaan gelap inilah seseorang akan terjerumus pada kesalahan yang
dianggap sebagai kebenaran. Keadaan seperti ini yang banyak terjadi pada para
filosof Barat.
Menyucikan jiwa merupakan langkah pengembalian fungsi jiwa kepada
hakikatnya, yaitu meletakkan jiwa kepada keadaan, peran dan fungsi sebagaimana
mestinya. Dalam kondisi ini, jiwa menjadi suatu hakikat yang bijak dan jauh dari
berbagai kecenderungan-kecenderungan yang menghalangi pada pencapaian
kebenaran. Pada saat seperti ini, akal menjadi mampu mengambil sikap yang tepat
menilai segala sesuatu sebagaimana fakta yang benar-benar sesuai dengan
keadaan.90
Murtaḍá menyebutkan bahwa kesucian menjadi penyebab
keharmonisan atau keseimbangan antara hati dan akal, sehingga keduanya dapat
menangkap kebenaran objektif.91
Hanya dengan keseimbangan itu seseorang dapat
menangkap kebenaran yang sesungguhnya.
Jiwa yang suci sebenarnya dapat mencegah kecenderungan-kecenderungan
hati dalam menilai sesuatu. Ketika dalam jiwa telah terjadi kecenderungan, maka
kecenderungan tersebut kemudian menguasai akal, keadaan itu menghalangi akal
untuk menangkap objek sebagai mana mestinya.92
Lebih detail Murtaḍá
menjelaskan bahwa setiap orang dapat menerima kebenaran dan pada saat itu pula
ia dapat menolaknya. Akal bisa menerima kebenaran dengan jelas dan gamblang
karena ada banyak bukti penguatnya, namun hati dan jiwanya dapat menolak
88
Murtaḍá Muṭahharī dan Ṭabáṭabáī, Menapak Jalan Spiritual. h. 72. 89
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Epistemologi Islam, h. 107. 90
Murtaḍá Muṭahharī, Ceramah-Ceramah Seputar Persoalan Penting Agama dan
Kehidupan. Penerjemah Ahmad Subandi, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), h. 289. 91
Murtaḍá Muṭahharī, Ceramah-Ceramah Seputar Persoalan Penting Agama dan
Kehidupan. Penerjemah Ahmad Subandi, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), h. 288. 92
Murtaḍá Muṭahharī, Ceramah-Ceramah Seputar Persoalan Penting Agama dan
Kehidupan. Penerjemah Ahmad Subandi, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), h. 292.
88
kebenaran itu karena keangkuhan dan kesombongan. Keangkuhan dan
kesombongan adalah tanda kekotoran jiwa.93
Hanya dengan kesucian jiwa, akal menjadi merdeka dari berbagai
kecenderungan baik berupa cinta, benci dan fanatisme lain. Akal yang bersih dan
akan menjadi objektif, dan di situlah seseorang dapat menemukan kebenaran yang
sesungguhnya. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin mengkaji suatu
pengetahuan hakiki (pengetahuan yang benar), hendaknya terlebih dahulu ia
menjadi seorang manusia sejati. Manusia sejati hanya didapatkan dengan
penyucian jiwa. Apa yang disampaikan oleh Murtaḍá merupakan ajaran Islam
yang tertuang dalam Q.S. al-Shams ayat 1-10.94
Penyucian jiwa oleh Murtaḍá disebut sebagai tazkiyatun nafs. Jiwa yang
suci akan menampakkan kepada manusia berbagai kebijaksanaan ilahi dan lainnya,
manusia dapat menyingkapnya dengan penyucian jiwa yang. Penyucian jiwa bagi
Murtaḍá merupakan sebuah cara untuk menangkap objek-objek transenden seperti
keilahian, jalan serta jalur yang mesti dilewati. Penyucian jiwa ternyata merupakan
sebuah cara yang ampuh dalam melenyapkan berbagai debu yang menghalangi
pandangan manusia terhadap kebenaran intuitif.95
2. Hal-hal yang Menghalangi Seseorang terhadap Kebenaran
Secara fitrah manusia mempunyai potensi untuk dapat mengetahui
berbagai objek sebagaimana adanya. Namun pada realitasnya terdapat tabir yang
menutupi objek sehingga ia tidak dapat mengetahuinya sebagaimana adanya.96
Hal-hal yang menghalangi tersebut di antaranya ialah :
a. Prasangka-prasangka97
Murtaḍá mengatakan bahwa persepsi tentang realitas yang didasarkan
kepada prasangka-prasangka yang belum pasti maka hal tersebut akan
mengantarkan seseorang kepada pengetahuan yang salah. Dalam mencari
kebenaran, seseorang hendaknya persepsi tentang realitas didasarkan kepada
pengetahuan pasti. Prasangka-prasangka akan menjadi semacam tabula yang
menjadi hijáb bagi kebenaran yang hendak dicapai.
Dalam rangka menguatkan apa yang dikatakannya, Murtaḍá kemudian
mengutip ucapan filosof, meskipun ia tidak menyebutkan nama filosofnya.
Dalam kutipannya dikatakan “aku baru menganggap sesuatu itu sebagai realitas,
kalau sesuatu itu sudah jelas bagiku. Aku tak mau tergesa-gesa, menghubungkan
gagasan dan kecenderungan. Aku hanya menerima apa yang sudah jelas bagiku,
sehingga tak ada lagi keraguan tentangnya. Tidak hanya itu, ia juga mengutip 2
ayat al-Qur‟an yaitu Q.S. al-An‟ám ayat 116 dan Q.S. al-Isra‟ ayat 36.
93
Murtaḍá Muṭahharī, Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam, (Bandung
Mizan, 2009), h. 320. 94
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Epistemologi Islam, h. 64-65. 95
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Epistemologi Islam, h. 61. 96
Murtaḍá Muṭahharī, Fitrah: Menyingkap Hakikat Potensi dan Jati Diri Manusia.
Penerjemah H. Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 65. 97
Murtaḍá Muṭahharī, Manusia dan Alam Semesta: Konsep Islam Tentang Jagat
Raya. Penerjemah Ilyas Hasan, (Jakarta: Lentera, 2002), h. 43-44.
89
b. Hawa Nafsu
Nafsu menjadi salah satu yang menghambat seseorang mencapai
kebenaran. Hawa nafsu dalam diri seseorang dapat membuat sikap seseorang
tidak netral dan cenderung kepada kekeliruan. Firman Allah dalam Q.S. An-
Najm ayat 23.
c. Tergesa-gesa
Untuk mencapai suatu kebenaran dibutuhkan berbagai argumen yang
kuat dan lengkap, maka kesimpulan yang tergesa-gesa akan menjerumuskan
seseorang kepada kekeliruan. Ketergesa-gesaan berpotensi melahirkan
kesimpulan yang tidak benar. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Isra‟ ayat
85 dan Q.S. Yūnus ayat 39.
d. Tepaku pada Masa Lalu
Murtaḍá menekankan bahwa berpikir independen sangat penting, karena
menerima begitu saja apa yang telah masa lalu lakukan belum tentu benar. Apa
yang telah dilakukan orang-orang masa lalu tidak dapat dipastikan benar. Allah
berfirman dalam Q.S. al-Baqarah 170.
e. Fanatisme
Murtaḍá mengatakan bahwa fanatisme merupakan satu hal yang
membuat jiwa dan pikiran menjadi berwarna. Ketika hati dan pikiran berwarna,
maka ia akan menangkap objek tidak sebagaimana mestinya, akan tetapi
menangkap objek sesuai dengan warna yang menodainya. Karena objek telah
ditangkap sesuai warna jiwa dan pikiran, maka pengetahuan tentang objek
tersebut dapat dipastikan tidak sesuai dengan apa yang ada.98
Maka pengetahuan
yang didapatkan adalah salah, karena tidak sesuai dengan yang ada.
Begitu pula kecintaan dan kebencian menurutnya akan merusak
kemurnian jiwa dan pikiran. Kecintaan dan fanatisme terhadap suatu tokoh
sebenarnya akan mempersempit jangkauan seseorang dalam mencapai
kebenaran. Fanatisme membuat cara berpikir seseorang tidak merdeka dan
menjadikan pola pikir seseorang menjadi tumpul. Padahal berbagai kemungkinan
salah masih sangat terbuka mengingat tokoh tersebut tidak maksum. Q.S. al-
Ahzáb ayat 67.99
Menanggapi tentang fanatisme terhadap tokoh, Muṭahharī menjelaskan
apa yang dikatakan oleh Ali. Ia menjelaskan bahwa kebenaran tidak diukur oleh
pribadi seseorang. Kebesaran seseorang, reputasi baik seseorang, atau hina
tidaknya seseorang tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur benar tidaknya apa
yang dia rumuskan. Menurutnya, kemuliaan dan kebesaran seseorang diukur
justru oleh kebenaran dari apa yang ia katakan dan lakukan. Penjelasan tersebut
kemudian dapat kita pahami bahwa kebenaran hanya dapat diukur oleh
98
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Epistemologi Islam, h. 167. 99
Murtaḍá Muṭahharī, Manusia dan Alam Semesta, (Jakarta: Lentera Basritama,
2002), h. 43-44.
90
kebenaran itu sendiri.100
Seseorang akan tahu orang yang benar ketika seseorang
telah menemukan kebenaran itu sendiri.
Kemudian Muṭahharī mengutip tulisan Michael Na‟imah tentang Imam
Ali. Kemudian Muṭahharī mengatakan bahwa Imam Ali merupakan contoh nyata
dari seseorang yang memasrahkan jiwa raganya bagi kebenaran di mana pun dan
dalam kondisi apapun. Maka Imam Ali merupakan suatu contoh bahwa
kebenaran akan memuliakan seseorang.101
Murtaḍá tampak ingin menjelaskan
bahwa Imam Ali merupakan sosok yang telah tahu akan kebenaran, sehingga ia
memasrahkan jiwa dan raganya pada kebenaran. Murtaḍá menggambarkan Imam
Ali sebagai contoh seseorang yang telah menemukan kebenaran.
100
Murtaḍá Muṭahharī, Tema-tema Pokok Nahj al-Balaghah. Penerjemah Arif
Mulyadi, (Jakarta: Islamic Center Jakarta, 2002), h. 26. 101
Murtaḍá Muṭahharī, Tema-tema Pokok Nahj al-Balaghah, h. 27.
91
BAB V
KRITIK MURTAḌÁ MUṬAHARĪ TERHADAP TEORI KEBENARAN
BARAT
A. Kritik Murtaḍá Muṭahharī terhadap Teori Kebenaran Karl Marx
Karl Marx adalah seorang filosof yang terkenal dengan filsafat
materialisme. Materialisme sebagai dasar berpikir Karl Marx untuk
mengembangkan konsep-konsep dalam berbagai dimensi kehidupan manusia
termasuk tentang kebenaran.1 Yang dimaksud dengan Materialisme ialah suatu
sistem pemikiran menjelaskan bahwa materi merupakan satu-satunya keberadaan
yang mutlak dan menolak keberadaan apapun selain materi. Konsep fakta ini yang
kemudian menjadi dasar dari teori kebenaran Karl Marx. Untuk membahas lebih
dalam mengenai hal tersebut, penulis akan sajikan teori Karl Marx mengenai
materialisme dialektika yang menjadi pokok pemikirannya. Materialisme
dialektika merupakan respons terhadap konsep manusia Hegel yang mengatakan
bahwa jiwa merupakan esensi dari manusia. Karl Marx menyanggah dan
mengatakan bahwa manusia adalah makhluk materi yang dapat dikaji secara
materi pula.2 Bisa dikatakan bahwa konsep materialisme Karl Marx merupakan
sebuah reaksi terhadap interpretasi idealistik Hegel terhadap kenyataan.3
Ide yang dikatakan Hegel sebagai penentu kebenaran dari berbagai hal,
oleh Karl Marx dijungkir balikkan. Karl Marx mengatakan bahwa realitas sejati
yang biasa dikatakan sebagai fakta berada di luar persepsi manusia, maka yang
menjadi penentu terakhir dari kebenaran ialah kenyataan materi. Bagi Marx,
kebenaran ide ditentukan oleh keberadaan objek materi. Sedangkan filsafat
idealisme menegaskan tentang kesadaran yang didasarkan pada ide-ide dan
mengingkari adanya realitas di belakang ide-ide manusia4 Pandangan ini sama
sekali tidak menyentuh kenyataan konkret masyarakat. Bukan alam yang
tergantung pada pikiran tetapi pikiran lah yang ditentukan oleh alam. Alam
menjadi dasar yang mutlak bagi pikiran. Marx menempatkan pengetahuan sebagai
proses-proses material. Proses-proses materi tersebut, jika dikaitkan dengan
masyarakat disebut sebagai kerja.5
Karl Marx mengkritik aktivitas manusia yang saat itu ia pahami sebagai
sosok yang selalu membentuk ide-ide salah tentang dirinya sendiri. Mereka
merancang hubungan-hubungan menurut ide-ide mereka sendiri tentang Tuhan,
tentang manusia. Hasil pemikiran telah terlepas dari tangan mereka, mereka
1 Fuadi, “Metode Historis: Suatu Kajian Filsafat Materialisme Karl Marx”, dalam
Substantia, vol. 17, No. 2, Oktober 2015, h. 220. 2 T. Z. Lavine, Pertualangan Filsafat dari Socrates ke Sartre, (Yogyakarta: Penerbit
Jendela, 2002), h. 46. 3 Yohanes Bahari, “Karl Marx, Sekelumit Tentang Hidup dan Pemikirannya”,
dalam Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, vol. 1, no 1, April 2010, h. 5. 4 Ali Maksum, Pengantar Filsafat dari Masa ke Masa Klasik Hingga
Posmodernisme, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), h. 154. 5 Sastria Wibowo, Kebenaran Sebagai Konstruksi Sosial, dalam Jurnal GEMA, vol.
30, no , April 2006, h. 102.
92
membungkukkan diri di bawah ciptaan.6 Karl Marx mengajak membebaskan
mereka dari tahayul-tahayul, ide-ide, dogma-dogma marilah melawan kekuasaan,
kaidah-kaidah atau konsep-konsep idealisme, dan sikap-sikap mengultuskan ide.
Akan tetapi Karl Marx menginginkan materi sebagai realitas empiris yang hakiki.
Konsep tersebut yang kemudian membuat Karl Marx dan pengikutnya tidak dapat
menerima kebenaran tentang keberadaan Tuhan, karena dianggap sebagai hayalan
dan tidak dapat dibuktikan secara materi.
Pandangan tersebut kemudian merambah kepada pandangan Marx tentang
sejarah yang kemudian dikenal dengan materialisme historis. Materialisme historis
berpendapat bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kedudukan materi, bukan
pada ide. Karl Marx menempatkan kata sejarah dengan maksud menjelaskan
berbagai tingkat perkembangan ekonomi masyarakat yang terjadi sepanjang
zaman. Sedangkan materialisme yang dimaksud Marx adalah mengacu pada
pengertian benda sebagai kenyataan yang pokok. Marx tetap konsekuen memakai
kata historical materialism untuk menunjukkan sikapnya yang bertentangan
dengan filsafat idealisme.7
Manusia sebagai makhluk sejarah hidup dalam kondisi-kondisi alam yang
berbeda. Metode historis harus dimulai dari dasar alamiah dan perubahan di
sepanjang sejarah melalui aktivitas manusia. Kondisi alamiah itu menentukan
seluruh tingkat perubahan, baik yang sifatnya perkembangan kemajuan maupun
kemunduran. Semua kondisi alamiah ini harus diungkapkan dengan metode
historis.8 Prinsip dasar teori ini ialah It is not consciousness that determines life,
but life that determines consciousness.9 “Bukan kesadaran manusia untuk
menentukan keadaan sosial, melainkan sebaliknya keadaan sosiallah yang
menentukan kesadaran manusia”.
Berdasarkan prinsip di atas, tampak jelas bahwa keterasingan manusia atas
dirinya yang memuja yang abstrak (seperti yang telah dijelaskan pada paragraf
awal), disebabkan oleh prilakunya sendiri. Tuhan yang selalu dipuja menurutnya,
hanyalah ciptaan manusia sendiri.10
Lebih lanjut Marx berkeyakinan bahwa untuk
memahami sejarah dan arah perubahan, tidak perlu memperhatikan apa yang
dipikirkan oleh manusia, tetapi bagaimana dia bekerja dan berproduksi.11
Dengan
6 Mansour Faqih, Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2002), h. 5. 7 Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern,
Posmodern, dan Poskolonial, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 45. 8 Djojohadikusumo Sumitro, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, (Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 1991), h. 209. 9 Jack Cohen dkk, (eds.), Marx and Engels Collected Works, vol. 5, (United
Kingdom: Lawrence and Wishart), h. 37. Lihat juga pada Elmadağ Polis Meslek Yüksek
Okulu, “Karl Marx and Ralf Dahrendorf: A Comparative Perspective on Class Formation
and Conflict”, dalam Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Iibf Dergisi, Agustus 2014, vol. 9,
no. 2, h. 158. 10
Daniel L Pals, Seven Theories of Religion, (New York: Oxford University Press,
1996), h. 133. 11
William Ebenstein, Isme-Isme yang Mengguncang Dunia: Komunisme, Fasisme,
Kapitalisme, Sosialisme, (Yogyakarta: Narasi, 2006), h. 13.
93
melihat cara manusia itu bekerja dan berproduksi. Dengan melihat cara manusia
itu bekerja dan berproduksi, dapat menentukan cara manusia berpikir.12
Karl Marx menekankan bahwa produksi merupakan dasar dari setiap
tatanan sosial. Maka kelas-kelas dalam tatanan masyarakat diklasifikasikan dan
ditentukan oleh apa yang dihasilkan, bagaimana ia dihasilkan, dan dipertukarkan.
Dalil pokok yang digunakannya dalam menganalisa masyarakat ialah penafsiran
ekonominya tentang historis. Produksi barang dan jasa merupakan yang membantu
manusia dalam hidupnya. Pertukaran barang-barang dan jasa-jasa ini adalah dasar
dari segala proses dan lembaga sosial. Karl Marx tidak menuduh faktor ekonomi
adalah satu-satunya yang penting dalam proses pembentukan historis. Ia
mendakwakan faktor ekonomi adalah yang terpenting sebagai dasar untuk
membangun superstruktur kebudayaan, perundang-undangan, pemerintahan, dan
diperkuat oleh ideologi-ideologi politik, sosial, keagamaan, kesusastraan dan
arsitek yang sejalan. Secara umum, Karl Marx melukiskan hubungan di antara
kondisi-kondisi materil kehidupan manusia dan ide-ide manusia.13
Apa yang
dikonsepsikan Marx tampak jelas ingin menekankan bahwasanya hanya materilah
yang dapat mengubah masyarakat.14
Bagi Karl Marx, kebenaran adalah sesuatu yang sungguh-sungguh praktis.
Aktivitas yang menjadi dasar hubungan manusia dengan dunia, yang membentuk
kebenaran adalah kerja. Pernyataan epistemologis yang terpenting baginya adalah
realitas sosial, politik, ekonomi yang dipikirkan oleh masyarakat semua itu
mempengaruhi situasi aktual dalam pekerjaan, dan akan mempengaruhi kebenaran
itu sendiri.15
Baginya, tindakan praktis manusia sangat penting bagi datangnya suatu
kebenaran, untuk itu ia mengemukakan mengenai masalah alienasi (keterasingan)
dalam dunia pekerjaan. Jika pekerjaan menjadi sarana perealisasi diri manusia,
seharusnya bekerja memberikan kegembiraan dan kepuasan. Namun, yang terjadi
justru sebaliknya. Untuk itulah sangat ditunggu tindakan praktis yang akan
menghancurkan alienasi dan mewujudkan kebenaran. Dengan demikian, kebenaran
menurut Marx adalah terwujudnya realitas sosial yang menghancurkan alienasi
tersebut. Kebenaran merupakan konstruksi sosial, yang mewujud dalam kesadaran
akan adanya alienasi dan menghancurkannya. Dalam konsepnya, Marx berbicara
kebenaran yang tidak muluk dan abstrak, tetapi hadir konkret di tengah kehidupan
masyarakat. Kebenaran harus membawa manusia pada kebebasan dan perwujudan
diri, yang dapat dirasakan langsung dalam suatu situasi sosial.16
Hal tersebut merupakan konsekuensi dari konsep materialisme Karl Marx
yang berkeyakinan bahwa segala macam gejala yang ada di dunia ini mempunyai
satu dasar yang sama, yaitu materi. D. N. Aidit menekankan bahwa dunia semesta
12
I. B. Wirawan, Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma, (Jakarta:
Prenadamedia, 2014), h. 10. 13
William Ebenstein, Isme-Isme yang Mengguncang Dunia ..., h. 6. 14
Irzum Farihah, “Filsafat Materialisme Karl Marx: Epistemologi Dialectical and
Historical Materialism”, dalam Fikrah, vol. 3, no. 2, Desember 2015, h. 439. 15
Wahyu Sastria Wibowo, “Kebenaran Sebagai Konstruksi Sosial”, h. 102. Lihat,
Richard Campbell, Truth and Historicity , (Oxford: Oxford University Press, 1992), h. 323. 16
Sastria Wibowo, Kebenaran Sebagai Konstruksi Sosial ..., h. 103.
94
ini pada hakikatnya adalah materi dan realitas materi ini adalah satu-satunya dunia
yang nyata.17
Ia kemudian menambahkan bahwa materi dalam kajian filsafat tidak
hanya terbatas pada benda-benda alam saja atau struktur dari segala sesuatu di
dunia, melainkan pula menyangkut berbagai hal yang ada di luar pikiran dan tidak
tergantung kepada kesadaran manusia, tidak diciptakan dan dikendalikan oleh
sesuatu ide apapun. Oleh karena itu, materi dalam pengertian Karl Marx ialah
meliputi juga gejala-gejala sosial.18
Penjelasan ini memberikan pengayaan
terhadap penjabaran tentang materialisme historis Karl Marx yang mengatakan
bahwa perubahan masyarakat disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri.
Perilaku di sini dengan jelas merupakan bentuk materi sebagaimana dijelaskan
oleh Aidit.
Murtaḍá Muṭahharī mengkritik konsep manusia yang digagas oleh
materialisme yang memandang manusia hanya dari sisi materinya tanpa
memandang kemungkinan jiwanya. Menurutnya memandang manusia dari segi
materinya saja, hanya akan memahami manusia sebagian saja. Menanggap
sebagian adalah keseluruhan jelas merupakan kekeliruan.19
Manusia bagi Murtaḍá
tidak hanya materi berupa badan dan prilakunya, melainkan juga terdiri dari jiwa.
Keduanya saling menyempurnakan. Tubuh dan jiwa menurutnya saling
mempengaruhi, maka antara sistem spiritual dan materi juga terjadi saling
hubungan yang sama. Murtaḍá memahami revolusi masyarakat bergerak menuju
kemerdekaan, kemandirian, dan supremasi jiwa yang semakin besar.20
Maka
konsep tentang manusia yang benar menurut Murtaḍá ialah konsep yang
menyentuh unsur materi maupun nonmateri. Maka dari itu, perubahan sosial yang
dikatakan oleh Marx adalah keliru, karena perubahan tersebut tidak hanya
dipengaruhi oleh prilaku dan hal materi, tetapi juga dipengaruhi oleh tatanan sosial
dan jiwa individu masyarakat yang juga ikut membentuk hidup manusia.
Pandangan Karl Marx tentang materi berimplikasi pada kepercayaan
mengenai keberadaan Tuhan. Menurutnya Tuhan hanyalah pelarian yang
diciptakan masyarakat karena kesulitan hidupnya yang sedang dilanda kemiskinan.
Oleh karena itu, Marx kemudian berkesimpulan bahwa Tuhan tidak ada. Pemikiran
itu jelas berangkat kegagalan Marx dalam membuktikanNya secara materi. Karena
Tuhan tak mempunyai realitas materi, maka jelas kebenaran tentang keberadaan
Tuhan adalah salah. Murtaḍá mengkritik pemikiran ini, baginya mengharapkan
Tuhan berada di laboratorium dan berada bersama benda-benda materi adalah hal
yang keliru karena Tuhan bukanlah materi. Mengukur keberadaan Tuhan dengan
indra adalah hal yang mustahil, karena ruang lingkupnya berbeda antara materi dan
nonmateri. Mengukur kebenaran Tuhan dengan indra, sama saja dengan mengukur
panas dengan penggaris. Mengukur panas dengan penggaris tidak akan pernah
17
D. N. Aidit, Tentang Marxisme, (Jakarta: Akademi Ilmu Sosial Aliarcham, 1962),
h. 29. 18
D. N. Aidit, Tentang Marxisme, h. 29. 19
Ahmad Maliki dan Damardjadi Supadjar, "Manusia dalam Eksistensialisme
Murtaḍá Muṭahharī”, dalam Humanika, vol. 18, no. 1, Januari 2005, h. 152. 20
Murtaḍá Muṭahharī, Manusia dan Alam Semesta. Penerjemah Ilyas Hasan,
(Jakarta: Lentera Basritama, 2002), h. 7-8.
95
sampai pada kebenaran, karena objek dan alat yang digunakan tidak tepat.21
Sama
halnya dengan mengukur kebenaran tentang keberadaan Tuhan.
Skema kekeliruan Karl Marx
Tuhan menurutnya tidak dapat dikaji melalui indra, melainkan langsung
dialami secara batin melalui hati. Hati dapat menangkap keberadaan Tuhan secara
objektif. Di samping itu juga tanda-tanda keberadaannya juga bisa didapatkan
melalui akal. Sesuatu yang tidak tampak dan tidak terlihat oleh mata, bukan berarti
ia tidak ada. Tidak semua orang yang mengakui kebenaran dari keberadaan
Amerika melihat langsung Amerika. Bagi mereka yang tidak pernah pergi ke
Amerika, kebenaran tentang keberadaan Amerika didapatkan melalui tanda-tanda
keberadaannya seperti dari berbagai informasi yang mutawattir dari orang-orang
dan melalui gambar-gambar hasil kamera. Kebenaran melalui tanda-tanda tersebut
oleh Murtaḍá tidak dikatakan sebagai kebenaran materi seperti yang dikatakan
oleh Karl Marx, tetapi ia merupakan kebenaran rasional, yang kebenarannya
didapatkan melalui argumen tanda-tanda yang didapatkan tentang hal tersebut.22
Murtaḍá membuktikan bahwa akal juga mampu mencapai kebenaran yang sama
seperti kebenaran yang dicapai oleh indra. Pada akhirnya pandangan kebenaran
tentang hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan juga sebagaimana kebenaran
materi. Hal tersebut adalah tanda bahwa tidak semua yang tidak bisa dilihat oleh
indra adalah tidak ada.
Dalam hal ini Murtaḍá tidak menolak kebenaran materi Karl Marx, yang ia
tolak adalah klaim bahwa yang hakiki hanyalah kebenaran materi dan secara
membabibuta mengukur segala realitas berdasarkan materi semata. Murtaḍá ingin
membuktikan bahwa kebenaran materi mempunyai batasan-batasan sesuai dengan
porsinya. Mata mempunyai batasan sejauh mata memandang, sama halnya dengan
indra-indra lain yang juga mempunyai batasan-batasan. Keterbatasan itu terbukti
pada butuhnya indra pada alat-alat lain seperti mikroskop untuk menambah daya
pandang mata.23
Pada aspek yang lain, kebenaran juga bisa didapatkan melalui
21
Murtaḍá Muṭahharī, Falsafath Kenabian. Penerjemah Ahsin Muhahham, (Jakarta:
Pustaka Hidayah. 1991), h. 94. 22
Murtaḍá Muṭahharī, Epistemologi Islam, h. 131. 23
Murtaḍá Muṭahharī, Filsafat Moral Islam: Kritik atas Berbagai Pandangan
Moral. Penerjemah Muhammad Babul Ulum dan Edi Hendri M, (Jakarta: al-Huda, 2004), h.
159.
96
akal dan intuisi.24
Sebagai mana telah dijelaskan oleh Murtaḍá, bahwa kebenaran
yang didapatkan melalui akal juga merupakan kebenaran hakiki sebagaimana
kebenaran materi yang diagungkan oleh Karl Marx. Pada pembahasan ini, Murtaḍá
mencontohkan kebenaran teori rasional dalam menemukan planet Neptune.25
Murtaḍá kemudian menambahkan, bahwa kebenaran materi yang
disampaikan Marx mempunyai keterbatasan sejauh mata menjangkau. Sehingga
terkadang, teori-teori materialisme tak mampu membaca suatu kebenaran tertentu
yang belum diteliti atau yang belum ia jangkau. Murtaḍá mencontohkan kebenaran
mu’jizat seperti kelahiran Nabi Isa. Kalau ditinjau dari perspektif materialisme,
kelahiran Nabi Isa dari Maryam adalah keliru dan bertentangan dengan ilmu
pengetahuan. Menurut Murtaḍá fenomena tersebut bukanlah kekeliruan. ia
kemudian mengatakan bahwa perbedaan suatu keadaan dengan teori ilmiah tidak
berarti keadaanlah yang keliru, karena alam tidak mungkin berjalan tanpa adanya
sistem atau hukum alam. Keadaan tersebut menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan
belum sampai pada tahapan tersebut. Mu’jizat tidak mungkin menabrak hukum
alam.26
Pada kesempatan berikutnya, Murtaḍá kemudian melanjutkan,
sesungguhnya perubahan hukum lama kepada yang baru bukanlah tanda bahwa
hukum yang lama itu keliru, namun hukum tersebut berganti kepada hukum baru
yang berbeda. Perbedaan itu disebabkan oleh perubahan objek dan syarat-syarat
yang tersedia. Jadi hukum yang lama benar sesuai dengan keadaan ketika
penelitian, kemudian hukum yang kedua benar sesuai dengan keadaan yang
terbaru. Dua hukum tersebut tidak saling menafikan, tetapi secara materi objeknya
telah berubah.27
Kebenaran materi sesungguhnya terikat dalam kerangka sejumlah
syarat tertentu dan terbatas, sehingga teori yang sama belum tentu bisa diterapkan
kepada objek yang sama dalam waktu dan keadaan yang berbeda, karena objek
tersebut juga telah ikut berubah sesuai perubahan waktu dan keadaan.
B. Kritik Murtaḍá Muṭahharī terhadap Teori Kebenaran René Descartes
René Descartes (1596-1650 M) merupakan tokoh rasional Barat yang
cukup terkenal. Ia mencoba mencari kebenaran yang hakiki melalui akal. Ia
berkeyakinan bahwa kebenaran dan kesesatan terletak dalam idea yang sudah
tertanam sejak ia lahir.28
Cogito ergo sum29
merupakan ungkapan yang menjadi
semboyan dalam teori kebenarannya. sedangkan metode dalam menemukan
24
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Filsafat Islam, h. 54. 25
Murtaḍá Muṭahharī , Pengantar Epistemologi Islam, h. 208. 26
Murtaḍá Muṭahharī, Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam. Penerjemah
Muhammad Abdul Mun’im al-Khaqani, (Bandung: Mizan, 2009), h. 130. 27
Murtaḍá Muṭahharī, Keadilan Ilahi ..., h. 129. 28
Ernita Dewi, “Meretas Makna Kebenaran Dalam Diskursus Filosofis”, dalam
Substantia, vol. 12, no. 1, April 2010, h. 350. 29
Cogito ergo sum merupakan pernyataan yang berasal dari bahasa latin. Arti dari
kalimat tersebut ialah aku berpikir, karena itu aku ada. Emma Dysmala Somantri,
“Epistemologi Hukum Islam Rasional-Empirik”, dalam Wawasan Hukum, vol. 26, no. 01,
Februari 2012, h. 490.
97
kebenaran disebut dengan “le daute methodique” (metode kesangsian).30
Mochammad Arifin mengatakan bahwa metode Descartes ini dalam kajian
epistemologi disebut dengan fondasionalisme, yaitu sebuah paham yang
mengatakan bahwa semua pengetahuan bertolak dari sebuah dasar atau fondasi
yang kebenarannya bersifat pasti dan berfungsi sebagai tolok ukur bagi semua
pengetahuan lainnya.31
Namun terdapat tambahan pendapat lain yang mengatakan
bahwa kepastian kebenaran tentang aku berpikir, maka aku ada didapatkan melalui
metode yang disebut sebagai Cartesian Doubt atau metode keraguan Descartes.32
Metode keraguan33
ialah proposisi apapun adalah salah (false) atau layak
dipertanyakan kebenarannya. Metode keraguan ini telah mampu mengantarkan
Descartes pada tahap pengetahuan yang kebenarannya tidak dapat diragukan lagi.
Keraguan menunjukkan suatu tindakan sikap mental murni yang
mempertanyakan dengan menanggapinya, ketidaksediaan untuk menyatakan atau
menerimanya. Descartes menggunakan keraguan untuk mulai mengatasi keraguan.
Salah satu cara untuk menentukan sesuatu yang pasti dan tidak dapat diragukan
ialah melihat seberapa jauh bisa diragukan. Keraguan bila diteruskan sejauh-
jauhnya, akhirnya akan membuka tabir yang tidak bisa diragukan, kalau hal itu
ada.34
Metode keraguan, pada dasarnya oleh Descartes hendak dijadikan suatu
tangga untuk menemukan metode yang ampuh dalam mencari kepastian dari
kebenaran hakiki suatu pengetahuan dan memastikan bahwa sesuatu yang ada itu
benar-benar ada dan bukan hanya khayalan semata. Metode ini kemudian menjadi
suatu fondasi dasar dari dalam rangka mencapai kebenaran yang hakiki.35
Descartes mengawali metode ini dengan meragukan dan menyingkirkan
berbagai keyakinan, pengalaman yang telah tertanam dalam diri kita.36
Menurut
Descartes kebenaran memang ada, namun itu dapat dikenal apabila jiwa kita bebas
dari pemikiran masa lalu, dan baru bernilai apabila secara metodis
diperkembangkan seperti dalam matematika.37
Hal tersebut menunjukkan bahwa
30
F. Budi Hardiman, Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzshe, (Jakarta:
Gramedia, 2007), h. 38. 31
Mochammad Arifin, “Epistemologi Rasionalisme Rene Descartes Dan
Relevansinya Terhadap Penafsiran al-Qur`An”, dalam Ilmu Ushuluddin, vol.17, no. 2, Juli-
Desember 2018, h. 148. 32
Ahmad Tafsir, Filsafat Umum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), h. 111 33
Keraguan adalah keadaan gelisah dan tidak puas dari mana kita berjuang untuk
membebaskan diri dan menjadi yakin, sedangkan yang keyakinan adalah keadaan tenang dan
puas yang mana kita tidak ingin menghindari atau untuk mengubah suatu kepercayaan apa
pun. Sebaliknya, kita berpegang teguh, bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk percaya apa
yang kita percaya. Afga Sidiq Rifai, “Kebenaran dan Keraguan dalam Studi Keislaman”,
dalam The Journal of Religious Research (JPA), vol. 20, no. 1, Januari-Juni 2019, h. 99. 34
Afga Sidiq Rifai, “Kebenaran dan Keraguan dalam Studi Keislaman”, dalam The
Journal of Religious Research (JPA), vol. 20, no. 1, Januari - Juni 2019, h. 99. 35
Cahaya Khaeroni, “Epistemologi Rasionalisme Rene Descarte Dan Relevansinya
Terhadap Pendidikan Islam”, dalam Didaktika Religia, vol. 2, no. 2 Tahun 2014, h. 189. 36
René Descartes, Meditations on First Philosophy, translator Elizabeth S. Haldane,
(Sydney: Cambridge University Press, 1911), h. 6. 37
Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2, (Yogyakarta: Penerbit Yayasan
Kanisius, 1980), h. 19.
98
Descartes berkeyakinan bahwa segala pengetahuan yang ada dalam diri seseorang
dapat diragukan. Cara untuk meragukan dan menolak berbagai pengetahuan
tersebut dapat dilakukan dengan menemukan alasan untuk meragukan pengetahuan
tersebut. Ketika kebenaran yang baru telah ditemukan dengan menggunakan alasan
tersebut, maka kebenaran pengetahuan yang lama yang berada dalam diri kita
dengan sendirinya akan hilang. Apapun yang “saya” terima sebagai hal yang
paling benar harus “saya” yakinkan baik dalam sense maupun melalui perasaan
tersebut. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, saya menemukan bahwasanya
perasaan dan sense “saya” ternyata menipu. Akan bisa bijak jika “saya” tidak
mempercayai orang atau apapun yang telah menipu saya.38
Begitulah perkataan
Descartes.
Ketika “saya” menyangsikan segala hal, setidaknya yang tidak dapat
disangsikan ialah bahwa “saya sedang menyangsikan”. Saya sedang menyangsikan
segala sesuatu merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diragukan lagi, ia
bukanlah tipuan. Justru kesangsian ini menurut Descartes, yang membuktikan
kepada diri kita bahwa kita adalah nyata. Selama kita ini sangsi, kita akan
merasakan makin pasti bahwa kita benar-benar nyata-nyata ada dan meyakinkan.
Meskipun mau dibahasakan dan ditutupi sedemikian rupa, kepastian bahwa “aku
yang menyangsikan” itu ada tak bisa dibantah.39
Kesangsian ini akan menyadarkan
kita bahwa saya sangsikan. Kesangsian secara langsung menyatakan adanya
saya.40
Sedangkan keberadaan saya merupakan kebenaran yang lahir dari keraguan
yang sudah tidak dapat diragukan. Dengan kata lain Descartes memahami
kebenaran hakiki menurutnya merupakan keraguan yang tidak dapat diragukan
lagi.41
Descartes menjadikan dalil keraguan sebagai dalil keyakinan, sebagaimana
pernyataan yang dikemukakan oleh Descartes ‛Meskipun saya meragukan indera
dan akal serta meragukan adanya alam semesta ini, namun dalam diri saya masih
tetap tegak satu hakikat yang tidak mungkin mengandung keraguan, karena hakikat
tersebut semakin menambah keyakinan setiap kali saya bertambah ragu. Hakikat
itu ialah sesungguhnya saya sedang ragu-ragu. Artinya saya sedang berpikir,
karena keraguan adalah pemikiran; sedangkan pemikiran hanya terjadi dari zat
yang sedang berpikir. Zat yang berpikir itu adalah saya, sehingga kalaupun saya
meragukan tentang apakah saya sedang berpikir ataupun tidak, tetapi keraguan itu
sendiri merupakan dalil bahwa saya sedang berpikir. Kebenaran itu menurutnya
adalah keraguan yang tidak dapat diragukan lagi.42
Puncaknya Descartes sampai
pada ketetapan tentang adanya Tuhan dan mengetahui semua sifat
kesempurnaannya yang mesti ada menurut akal pikiran. Descartes merasa yakin,
38
René Descartes, Meditations on First Philosophy, h. 7. 39
F. Budi Hardiman, Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche,
(Jakarta: Gramedia, 2007), h. 38. 40
Berlen, Ringkasan Sejarah Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1979), h. 45. 41
Ernita Dewi, “Meretas Makna Kebenaran dalam Diskursus Filosofis”, dalam
Substantia, vol. 12, no. 2, Oktober 2010, h. 350. 42
Mursyid Fikri, “Rasionalisme Descartes dan Implikasinya Terhadap Pemikiran
Pembaharuan Islam Muhammad Abduh”, dalam Tarbawi, vo. 3, no. 2, Juli-Desember 2018,
h. 136.
99
semua kebenaran itu ada dan kebenaran-kebenaran tersebut dikenal dengan cahaya
yang terang dari akal budi.43
Kebenaran dapat dipahami melalui perantara khusus
yang diperoleh dengan teknik deduktif.
Penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Descartes begitu
meyakini kebenaran yang hakiki hanya didapatkan melalui proses rasional dengan
metode kesangsian. Secara otomatis, berbagai pengetahuan di luar itu telah
terbukti membuat Descartes tertipu sehingga dapat diragukan kebenarannya.
Ketika keraguan itu muncul, maka pada saat itu pula pengetahuan itu bukanlah
kebenaran, karena baginya kebenaran adalah sesuatu yang pasti dan meyakinkan.
Dalam suatu kebenaran, tidak terdapat keraguan sedikit pun. Akal mempunyai
kedudukan istimewa bagi Descartes, hingga ia mengatakan bahwa tanpa
pengalaman, akal dengan mandiri sebenarnya mampu menemukan pengetahuan
(kebenaran). Menurut Descartes aktivitas akal sebenarnya lebih dulu dari
pengalaman inderawi, inilah yang kemudian ia sebut sebagai kebenaran apriori.
Dalam teori Innatenya Descartes menyatakan, sejak manusia lahir, akal sebenarnya
sudah punya norma-norma atau standar-standar yang bisa membimbing
pemiliknya untuk menemukan pengetahuan (kebenaran).44
Konsep Descartes tentang keraguan terhadap diri dibantah oleh Murtaḍá.
Murtaḍá mengkritiknya dengan menjelaskan bahwa mengetahui diri sendiri
menurut Murtaḍá ialah fitrah. Lahirnya ego sama dengan lahirnya sadar diri. Ego
adalah realitas. Realitas itu sendiri ialah mengenal diri. Maka pengetahuan seperti
ini tidak dapat dibayangkan keraguannya. Maka mustahil adanya keraguan dalam
kasus seperti ini. Di sinilah Descartes melakukan kesalahan yang sangat
fundamental. Dia tidak tahu bahwa “aku ada” tak menimbulkan keraguan,
sehingga tidak perlu meniadakannya dengan perkataan “aku berpikir, maka aku
ada”.45
Selain itu Murtaḍá menyoroti pandangan Descartes yang menolak indra
sebagai salah satu instrumen dalam meraih kebenaran, maka baginya tidak ada
kebenaran materi. Hal tersebut dibantah oleh Murtaḍá bahwa instrumen
pengetahuan tidak hanya indra, tetapi akal dan hati. Itu berarti kebenaran tidak
hanya didapatkan melalui akal, melainkan juga dengan indra dan hati.46
Menurut
Murtaḍá kita tidak dapat menafikan apa yang memang sudah nyata kita tahu dan
alami tentang fungsi indra dan hati dalam meraih kebenaran. Menurut Murtaḍá,
fakta tentang garam asin merupakan suatu kebenaran hakiki yang tidak bisa kita
pungkiri. Ia menambahkan seseorang tidak dapat memungkiri adanya siang dan
malam. Kesemuanya merupakan kebenaran empiris, di mana kebenarannya
didapatkan melalui pengalaman langsung melalui indra.47
Hal tersebut dapat
43
Harry Hamersma, Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern, (Jakarta: Gramedia,
1992), h. 8. 44
Aguk Irawan MN, “Filsafat Pragmatisme-Kontemporer: Ikhtiar Awal Memahami
Teori Charles Sanders Peirce”, vol.10, no.1, September 2013, h, 4. 45
Murtaḍá Muṭahharī, Manusia dan Alam Semesta. Penerjemah Ilyas Hasan,
(Jakarta: Lentera Basritama, 2002), h. 250. 46
Murtaḍá Muṭahharī, Epistemologi Islam, h. 57. 47
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Filsafat Islam: Filsafat Teoritis dan Filsafat
Praktis. Penerjemah M. Ilyas, (Yogyakarta: Rausyanfikr, 2003), h. 72.
100
dibuktikan dan diuji kebenarannya oleh orang lain. Suparlan dalam bukunya
mendukung pernyataan ini, kebenaran materi juga kebenaran hakiki yang ruang
lingkupnya sesuai dengan objek yang bersifat materi.48
Di samping itu pula, menurut Murtaḍá mengkritik teori Descartes tentang
akal sebagai satu-satunya sumber kebenaran. menurut Murtaḍá, akal memang ada
kalanya dapat membuktikan kebenaran secara pasti seperti adanya kepastian
tentang hasil dari 2+2 adalah 4. Tanpa indra pun akal dapat menemukan kebenaran
itu secara pasti dan meyakinkan. Namun pengetahuan tentang penjumlahan
tersebut bukan telah tertanam sejak lahir seperti yang dikatakan Descartes,
melainkan ia lahir seiring dengan pertumbuhan dalam mempelajari hal-hal yang
bersifat rasional. Pada mulanya manusia tidak mempunyai pengetahuan tentang
apapun, baru kemudian pada perkembangannya, pengetahuan mereka terus
bertambah.49
Hal tersebut dikuatkan bahwa anak yang masih kecil, belum belajar
tentang hal tersebut, maka ketika kita bertanya kepadanya mengenai penjumlahan
tersebut, maka anak kecil tersebut tidak bisa menjawabnya. Jika memang
pengetahuan tersebut sudah ada sejak lahir, seharusnya anak kecil sudah tahu
tentang penjumlahan tersebut.
Kritik berikutnya ialah bahwa berbagai teori kebenaran tertanam dalam
akal manusia, semuanya lahir dari akal itu sendiri, begitu kata Descartes. Murtaḍá
membantahnya dengan mengatakan bahwa teori-teori abstrak (konsep rasional)
yang tertanam di dalam akal seseorang, adakalanya merupakan abstraksi dari objek
indra atau materi yang pada tahap tertentu telah kehilangan sifat dan identitas
materinya.50
Di antaranya ialah teori-teori yang berkaitan dengan benda-benda
materi seperti konsep tentang kucing hitam. Karena konsep tersebut berasal dari
materi, maka untuk menguji kebenaran konsep tersebut, juga harus diverifikasi
kesesuaian konsep tersebut dengan materi yang bersangkutan. Murtaḍá
menekankan bahwa kebenaran pada dasarnya mempunyai ranah yang berbeda-
beda berdasarkan pada objek kajiannya. Kebenaran materi yang berkaitan dengan
indra dan objek materi hanya dapat dibuktikan melalui pengamatan indra.
Demikian pula dengan kajian yang bersifat rasional, yang hanya bisa dibuktikan
melalui dialog antar teori dalam akal.
C. Kritik Murtaḍá Muṭahharī terhadap Teori Kebenaran Auguste Comte
Auguste Comte (1798–1857 M) adalah salah satu tokoh positivisme yang
melandaskan pemikirannya pada fakta-fakta yang teramati.51
Dalam hal
pengetahuan, Auguste Comte tampaknya hanya menerima pengetahuan yang
bersifat faktual. Ia memahami fakta sebagai sesuatu yang lepas dari kesadaran
individu. Fakta positif merupakan suatu fakta yang riil, nyata dan dapat diuji atau
48
Suparlan Suhartono, Filsafat Ilmu Pengetahuan: Persoalan Eksistensi dan
Hakikat Ilmu Pengetahuan, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2005), h. 82. 49
Murtaḍá Muṭahharī, Fitrah: Menyingkap Hakikat, Potensi dan Jati Diri Manusia,
(Jakarta: Lentera, 2008), h. 45. 50
Murtaḍá Muṭahharī, Teori Pengetahuan: Catatan Kritis Atas Berbagai Isu
Epistemologis, penerjemah Muhammad Jawad Bafaqih, (Jakarta: Sadra Press, 2019), h. 76. 51
F. Budi Hardiman, Filsafat Modern, h. 204.
101
diverifikasi oleh setiap orang yang mau membuktikannya.52
Kenyataan baginya
adalah segala hal yang faktual. Karena kenyataan yang diakui Comte hanyalah
yang aktual empiris saja, maka pengetahuan dan konsep yang benar hanyalah yang
berlandaskan pada objek faktual.53
Hal ini yang kemudian Auguste Comte dapat dikategorikan sebagai filosof
empirisme. Kaum Empiris meyakini bahwa semesta adalah segala sesuatu yang
hadir melalui data inderawi, dengan kata lain pengetahuan manusia harus berawal
dari pengamatan empiris-inderawi. Positivisme mengembangkan klaim empiris
tentang pengetahuan secara ekstrem dengan mengatakan bahwa puncak
pengetahuan manusia adalah ilmu-ilmu berdasarkan pada fakta-fakta keras, terukur
dan teramati.54
Comte mengatakan bahwa suatu pembawa kebenaran dapat
dikatakan benar manakala pernyataan itu telah diverifikasinya hingga sampai pada
kebenaran yang dimaksud.55
Dampak dari pemikirannya yang hanya menerima
kebenaran pengetahuan yang berdasarkan pada fakta positif itu kemudian
menjadikannya menolak berbagai pengetahuan di luarnya, termasuk kebenaran
metafisik.
Di tengah pemikiran yang begitu materialistik, Comte menyebutkan bahwa
masyarakat sebenarnya mengalami proses-proses yang terus menerus mengalami
perubahan sesuai dengan konsensus. Masyarakat menurutnya disatukan dalam
naungan sebuah konsensus. Penerapan metode positif dalam masyarakat tersebut
menjelaskan kepada kita bahwa dalam metode positif terdapat peran kesepakatan
dalam menentukan kebenaran. Hal ini akan melahirkan bahwa ketika suatu teori
secara empiris dianggap benar oleh masyarakat, maka di saat itu pula teori tersebut
benar adanya. Dalam kesempatan yang berbeda, kebenaran tersebut bisa berbeda
dengan yang pertama ketika masyarakat telah menyepakati teori yang berbeda.
Maka kedua kebenaran yang dianggap oleh masyarakat yang berbeda tersebut
sama-sama menemukan kebenaran berdasarkan masyarakat tertentu yang memang
berbeda.56
Pemikiran ini kemudian dikritik oleh Murtaḍá. Comte tampaknya lupa
bahwa pada dasarnya fakta dipengaruhi oleh sudut pandang seseorang. Fakta yang
dijadikan landasan kebenaran Comte merupakan perspektif dari manusia tentang
suatu fakta. Maka sesungguhnya pada setiap masa, pandangan tentang fakta akan
terus mengalami perubahan sesuai dengan kemampuan dan kondisi manusia. Maka
secara tidak langsung, kebenaran yang dirumuskan oleh Comte adalah kebenaran
yang disepakati. Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah diungkapkan
Muhammad Chabibi, yang mengatakan bahwa kebenaran menurut Comte
52
Koento Wibisono. Arti Perkembangan menurut Positivisme Comte, (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 1996), h. 17. 53
F. Budi Hardiman, Filsafat Modern, h. 213. 54
Muhammad Chabibi, “Hukum Tiga Tahap Auguste Comte dan Kontribusinya
terhadap Kajian Sosiologi Dakwah”, dalam Nalar, vol. 3, no. 1, Juni 2019, h. 15-16. 55
Ichwan Supandi Aziz, "Karl Raimund Popper dan Auguste Comte (Suatu
Tinjauan Tematik Problem Epistemologi dan Metodologi)”, dalam Jurnal Filsafat, no. 3,
Desember 2003, h. 256. 56
Muhammad Chabibi, “Hukum Tiga Tahap Auguste Comte dan Kontribusinya
terhadap Kajian Sosiologi Dakwah”, h. 17.
102
ditentukan oleh seberapa besar masyarakat menerima dan bersepakat atas
kebenaran tersebut. Teori bumi sebagai pusat orbit tata surya yang dirumuskan
oleh Ptolemaios merupakan kebenaran. Teori Copernicus dan Galileo juga
merupakan suatu kebenaran, karena masyarakat menerimanya sesuai dengan
masanya.57
Hal semacam ini dikritik oleh Murtaḍá. Menurut Murtaḍá kebenaran
adalah tidak plural dan tidak mengalami perubahan-perubahan.58
Kritik Murtaḍá terhadap Comte tampaknya salah alamat, karena kebenaran
yang dihasilkan dari kesepakatan masyarakat tersebut tampaknya berlaku pada
praktek metode sains positivis terhadap realitas sosial yang begitu kompleks dan
mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ilmu alam. Menurut Ulfatun
Hasanah, Perbedaan karakteristik antara ilmu alam dan sosial ialah sebagai berikut.
(1) gejala sosial lebih kompleks dibandingkan gejala alam. Jika seorang guru,
misalnya, menghukum anak didiknya dengan merotan, maka hukum-hukum ilmu
kimia, ilmu alam dan ilmu fisiologi mungkin mampu menerangkan sebagian dari
kejadian tersebut, tetapi hal yang lebih asasi dari itu tidak akan terjangkau oleh
penjelasan tersebut, (2) seorang ahli ilmu kimia atau ahli fisika bisa mengulangi
kejadian yang sama tiap waktu dan mengamati suatu kejadian secara langsung,
sedangkan ahli ilmu sosial tidak mungkin melihat, mendengar, meraba, mencium
atau menangkap gejala yang sudah terjadi di masa lalu. Seorang ahli ilmu jiwa
tidak mungkin mencampurkan ramuan-ramuan ke dalam tabung reaksi untuk bisa
merekonstruksi masa kanak-kanak seorang manusia dewasa, (3) gejala fisik pada
umumnya bersifat seragam dan gejala tersebut dapat diamati sekarang, sementara
gejala sosial banyak yang unik, kompleks dan sukar untuk terulang, (4) gejala fisik
seperti halnya unsur kimia bukanlah suatu individu, melainkan suatu barang mati,
sehingga ahli ilmu alam tidak perlu memperhitungkan tujuan atau motif dari planet
atau lautan. Akan tetapi, seorang ahli ilmu sosial harus mempelajari manusia yang
memiliki tujuan, keinginan dan pilihan, sehingga gejala sosial selalu berubah
sesuai dengan tindakan manusia yang didasari keinginan dan pilihan tersebut.59
Penjelasan Ulfatun memberikan penjelasan kepada kita bahwa dalam ilmu
pengetahuan sosial memang berlaku perubahan-perubahan fakta yang disebabkan
oleh pengaruh keinginan, tujuan dan pilihan kolektif dari manusia. Di situlah
sebenarnya lahir kesepakatan-kesepakatan dan perubahan dari masa ke masa yang
kemudian berdampak kepada kebenaran dari teori tersebut. Inilah yang disoroti
oleh Murtaḍá. Akan tetapi pada dasarnya Auguste Comte berbeda dalam
menyikapi pengetahuan alam tidaklah sama, karena objeknya merupakan benda
mati yang tak memeliki perubahan-perubahan keinginan.
Pada paragraf selanjutnya Ulfatun melanjutkan dengan kalimat yang
tampak seperti bertentangan dengan yang ia utarakan. Menurutnya meskipun teori
kebenaran pengetahuan positivis dilandaskan pada kenyataan faktual, namun
pengetahuan kita pada prinsipnya tak pernah selesai dan relatif, sesuai dengan sifat
57
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Epistemologi Islam, h. 221-222. 58
Murtaḍá Muṭahharī, Filsafat Hikmah: Pengantar Kepada Pemikiran Sadra,
Penerjemah Tim Penerjemah Mizan, (Bandung: Mizan, 2002), h. 77. 59
Ulfatun Hasanah, “Kontribusi Pemikiran Auguste Comte (Positivisme) terhadap
Dasar Pengembangan Ilmu Dakwah”, dalam Al-I’lam, vol. 2, no 2, Maret 2019, h. 75.
103
relatif dan semangat positif.60
Pandangan ini mengarah kepada teori kebenaran
pengetahuan sains positivis. Pendapat ini kemudian dikuatkan oleh Chabibi yang
mengatakan bahwa pada tahap perkembangan manusia pada level tertinggi yang
Comte sebut sebagai tahap positif, manusia tampil sebagai sosok yang percaya
terhadap data-data empiris sebagai sumber akhir dari kebenaran pengetahuan.
Namun yang menarik ialah Chabibi mengatakan bahwa kebenaran tersebut bersifat
sementara dan tidak mutlak.61
Pandangan ini merupakan argumen yang ikut serta dalam menguatkan
pendapat Murtaḍá yang mengatakan bahwa pandangan Comte tentang kebenaran
adalah relatif. Maka dari itu, Murtaḍá mengatakan bahwa kebenaran yang relatif
tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena akan terdapat kebenaran yang
berubah-ubah dan akan melahirkan lebih dari satu kebenaran dalam waktu dan
kondisi yang berbeda. Dalam pandangan Murtaḍá Muṭahharī, kebenaran adalah
tidak berubah dan hanya satu. Jadi ketika ada dua teori tentang suatu hal, maka
salah satu dari teori tersebut adalah keliru.62
Murtaḍá kemudian memberikan contoh kekeliruan tentang kebenaran
relatif yaitu tentang relativisme suhu yang dirasakan dua individu dalam kondisi
dan keadaan yang berbeda. Pada air dengan suhu tertentu (800), dua orang yang
berbeda akan merasakan temperatur yang berbeda. Ketika orang kedua kondisi
tangannya sebelum menyentuh air, ia memegang es, maka ia akan merasakan suhu
lebih dingin dari pada orang pertama. Pada saat itu akan muncul dua kebenaran
yang berbeda. Kebenaran tersebut menurut Murtaḍá adalah semu, karena suhu
yang sebenarnya adalah 800. Di situlah sebenarnya kebenaran merupakan hal yang
tidak berubah dan satu. Itulah yang disebut kebenaran hakiki oleh Murtaḍá.63
Kritik lain dari Murtaḍá terhadap Comte ialah tentang fanatisme Auguste
Comte terhadap kebenaran positif. Sebenarnya dalam kritik ini, Murtaḍá tidak
menyebut nama Comte secara spesifik. Ia hanya mengkritik berbagai pandangan
yang fanatik pada satu pandangan kebenaran yang kemudian menolak pandangan
kebenaran hakiki lainnya.
Di berbagai literatur telah disebutkan bahwa Auguste Comte dengan teori
positifnya telah memberikan implikasi yang luar biasa, bahwa kebenaran selain
kebenaran positif tidak dapat dikatakan sebagai kebenaran hakiki, karena ia anggap
sebagai pengetahuan yang melebihi kenyataan faktual berupa materi. Jika memang
demikian, maka manusia akan kehilangan banyak pengetahuan, karena pada
kenyataannya manusia menganut pengetahuan yang tak berkaitan dengan objek
empiris. Menurut Murtaḍá, selain kebenaran positif yang dikatakan Comte,
terdapat beberapa kebenaran hakiki yang seharusnya juga diterima sebagai
kebenaran sebagaimana kebenaran teori positif. Kebenaran tersebut di antaranya
ialah kebenaran rasional dan kebenaran metafisik.64
60
Ulfatun Hasanah, “Kontribusi Pemikiran Auguste Comte (Positivisme) terhadap
Dasar Pengembangan Ilmu Dakwah”, h. 75. 61
Muhammad Chabibi, “Hukum Tiga Tahap Auguste Comte dan Kontribusinya
terhadap Kajian Sosiologi Dakwah”, h. 20. 62
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Epistemologi Islam, h. 251. 63
Murtaḍá Muṭahharī, Pengantar Epistemologi Islam, h. 251-253. 64
Murtaḍá Muṭahharī, Manusia dan Alam Semesta, h. 188.
104
Manusia tidak dapat menolak kebenaran dua kebenaran tambahan ini,
karena fakta pengetahuan tidak hanya bersifat materi belaka, namun juga bersifat
non materi berupah objek akal dan objek hati yang metafisik. Hal tersebut juga
merupakan suatu realitas. Setelah ditelusuri lebih dalam, Comte ternyata juga
menerima pengetahuan yang bersifat rasional, meskipun dalam teori positifnya ia
menolak berbagai pengetahuan di luar positif. Ketika ia membagi pengetahuan,
Comte justru menjadikan matematika sebagai salah satu pengetahuan yang paling
valid yang kebenarannya tak dapat diragukan dan bahkan matematika oleh Comte
dianggap sebagai dasar ilmu yang lain.65
Bukankah matematika merupakan bagian
dari pengetahuan yang tak berobjek kasar.
Irham Nugroho mempunyai pendapat yang berbeda mengenai pembagian
matematika sebagai ilmu. Irham justru mengatakan bahwa Comte tidak
mengategorikan matematika sebagai sebuah ilmu pengetahuan layaknya biologi,
melainkan suatu alat berpikir logik.66
Meskipun Comte memandang matematika
bukanlah ilmu, tetapi ia memberikan posisi yang begitu tinggi kepada matematika
hingga logika ia klaim mempunyai peranan yang amat penting dalam rangka
pengelolaan data-data empiris yang didapatkan melalui pengalaman langsung pada
objek materi. Pandangan Ichwan Supandi Aziz ini tampak sejalan dengan pendapat
Irham mengenai status matematika dalam teori positivis.67
Jika kita amati tulisan Comte yang telah ditulis ulang oleh Harriet
Martineau dengan berjudul The Positive Philosophy of Auguste Comte, dijelaskan
bahwa Comte menyebut matematika sebagai perfect science. Secara jelas Comte
mengatakan bahwa matematika merupakan bagian dari ilmu (science).68
Penyebutan istilah ilmu atau sains terhadap matematika tidak hanya satu kali,
melainkan beberapa kali seperti yang di tuliskan pada halaman yang sama ia
menyebut dengan istilah science of Magnitudes. Pada halaman 67 ia kembali
menyebut matematika sebagai ilmu dengan istilah mathematical science.69
Berdasarkan ini, tampak jelas bahwa Comte menganggap matematika sebagai
sains seperti biologi dan lainnya.
Meskipun Comte benar-benar tidak menjadikan matematika sebagai ilmu,
namun menurut Horkheimer, Comte sebarnya tidak konsisten dengan teorinya dan
ia menganggap Comte telah diam-diam membangun sebuah teori yang begitu
kontemplatif dan membangun mitos baru berupa rasionalitas instrumental.70
Ketika
Comte menganalisa masyarakat sosial menggunakan teori positif, di situlah Comte
telah memasukkan nilai-nilai masyarakat yang kemudian melahirkan perubahan-
65
Harry Hamersma, Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern, h. 56. 66
Irham Nugroho, “Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis dan Nilai
Etisnya Terhadap Sains”, dalam Cakrawala, vol. xi, no. 2, Desember 2016, h. 172. 67
Ichwan Supandi Aziz, "Karl Raimund Popper Dan Auguste Comte (Suatu
Tinjauan Tematik Problem Epistemologi dan Metodologi)”, dalam Jurnal Filsafat, no. 3,
Desember 2003, h. 254. 68
Harri Martineau, The Positive Philosophy of Auguste Comte, (Kitchener: Batoche
Books, 2000), h. 56. 69
Harri Martineau, The Positive Philosophy of Auguste Comte , h. 67. 70
Luthfiyah, “Kritik Modernitas Menuju Pencerahan: Perspektif Teori Kritis
Mazhab Frankfurt”, dalam Tajdid, vol. 2, no. 1, April 2018, h. 281-282.
105
perubahan pada teori tersebut. hal ini menunjukkan inkonsistensi Comte yang pada
awalnya mengatakan bahwa kebenaran hakiki adalah bebas nilai. Di sinilah
sebenarnya teori kebenaran pengetahuan yang dibangun Comte pada dasarnya
telah melebihi realitas faktual itu sendiri. Oleh karena itu, Comte telah melanggar
aturan yang dibuatnya sendiri.71
Penjelasan di atas menjelaskan bahwa kebenaran bagi Murtaḍá tidak hanya
didapatkan pada pengetahuan yang diraih oleh pancaindra, namun juga terdapat
kebenaran lain yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan seperti
kebenaran logis dan kebenaran metafisik. Keduanya adalah kebenaran yang
mempunyai ranah masing-masing. Cara membuktikannya pun sesuai dengan
ranahnya, sehingga kebenaran tentangnya akan tersingkap.
71
Ulfatun Hasanah, “Kontribusi Pemikiran Auguste Comte (Positivisme) terhadap
Dasar Pengembangan Ilmu Dakwah”, h. 77.
107
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Diskusi tentang teori kebenaran Murtaḍá Muṭahharī telah disajikan dari bab
i hingga bab v. Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebenaran
menurut Murtaḍá Muṭahharī merupakan persesuaian antara pembawa kebenaran
dengan hakikat sebagaimana adanya. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa
kebenaran terletak pada sejauh mana subjek mempunyai pengetahuan tentang objek.
Murtaḍá mengatakan bahwa objek tidak hanya berupa materi, tetapi juga bisa berupa
hal yang bersifat rasional dan intuitif. Kebenaran yang bersifat materi dapat
dibuktikan dengan adanya persesuaian tentang adanya konsep siang dan malam yang
kemudian dapat dibuktikan oleh indra bahwa terdapat siang dan malam. Namun juga
terdapat realitas yang tak bersifat materi seperti segi empat. Segi empat adalah
realitas immateri yang dalam menguji kebenarannya menggunakan argumen
rasional. Segi empat dapat dikatakan benar bukan karena ada materi yang berbentuk
segi empat, namun segi empat dikatakan benar ketika ia bersesuaian dengan konsep
rasional yang sudah baku mengenai karakteristik segi empat. Begitu pula dengan
kebenaran intuitif, seperti hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan secara mendalam tidak
dapat dicapai melalui pengelaman empiris maupun rasional karena bersifat
transenden. Maka kebenaran tentang hakikat Tuhan, hanya bisa dicapai melalui
pengalaman spiritual secara langsung melalui hati. Kesemua kebenaran tersebut
tidak saling bertentangan, justru akan saling melengkapi karena antara satu dengan
yang lainnya mempunyai ranah masing-masing. Pembeda antara teori kebenaran
Murtaḍá dengan yang lain ialah Murtaḍá mengkompromikan teori kebenaran Islam
dan Barat yang pada mulanya saling meniadakan. Murtaḍá mengambil sisi
kebenaran yang ada pada teori Barat.
Kritik Murtaḍá mengacu pada pandangan Barat yang menerima kebenaran
hanya dari satu aspek dan menolak kebenaran lainnya, pencampuradukan metode
pembuktian kebenaran dengan objek yang tak seharusnya, sehingga menghasilkan
teori yang salah. Demikian juga kritiknya terhadap Karl Marx. Ia mengatakan bahwa
Marx telah melakukan kesalahan karena telah mengukur semua kebenaran
berdasarkan materi belaka dan membuktikan kebenaran objek immateri seperti
kebenaran Tuhan dengan pembuktian berdasarkan indra. Menurut Murtaḍá
membuktikan objek yang bersifat immateri hanya bisa dibuktikan menggunakan alat
yang bersifat immateri pula seperti akal dan hati. Jika ingin mengetahui kebenaran
tentang keberadaan Tuhan, maka dengan logika melalui tanda-tanda yang telah ada.
Jika ingin Tahu secara langsung tentang kebenaran Tuhan, maka harus mengalami
langsung secara batin. Kritik Murtaḍá terhadap Descartes tertuju pada teori
Descartes yang mengatakan bahwa satu-satunya tolok ukur kebenaran sudah
tertanam dalam benak seseorang sejak lahir. Murtaḍá mengatakan yang ada sejak
lahir dalam diri seseorang hanyalah potensi untuk mencapai kebenaran rasional.
Dalam perjalanan hidup manusia, potensi tersebut dapat diasah sehingga lahirlah
pengetahuan dan kebenaran seiring dengan perjalanan waktu. Berkaitan dengan
konsep Descartes tentang “aku berpikir, maka aku ada”, Murtaḍá menilai Descartes
108
telah melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut terdapat pada keraguan terhadap diri.
Menurut Murtaḍá, untuk mencapai kebenaran tentang keberadaan diri seseorang
tidak perlu meragukannya, karena keberadaan aku (yang oleh Murtaḍá juga disebut
dengan mengenal diri) tidak menimbulkan keraguan sama sekali, sehingga tidak
mungkin keberadaan diri dapat diragukan. Dengan meragukan diri itu,
sesungguhnya Descartes telah melakukan kesalahan fatal. Auguste Comte tentang
kebenaran empirisnya. Murtaḍá mengklaim bahwa kebenaran yang ditawarkan oleh
Comte adalah nisbi. Menurutnya pandangan yang ditawarkan oleh Comte adalah
kebenaran perspektif tentang fakta. Karena kebenaran tersebut adalah perspektif,
maka setiap saat akan terus mengalami perubahan, sesuai dengan kemampuan dan
kondisi manusia. Maka secara tidak langsung, teori positivisme Comte oleh Murtaḍá
diklaim sebagai kebenaran kesepakatan, karena landasan kebenarannya tergantung
sejauh mana, kebenaran tersebut diterima oleh masyarakat. Padahal menurut
Murtaḍá kebenaran tidak mengenal masa dan perubahan. Kebenaran bagi Murtaḍá
ialah tidak mengalami perubahan.
B. Kritik dan Saran
1. Kritik
Dalam membahas teori kebenaran, Murtaḍá menjelaskan bahwa terdapat
hal-hal yang dapat menghalangi seseorang sampai pada kebenaran hakiki. Salah
satu dari hal-hal tersebut ialah fanatisme. Dalam kajian fanatisme Murtaḍá
menekankan bahwa fanatisme terhadap apapun, baik terhadap tokoh maupun
madzhab akan menghalangi seseorang pada kebenaran. Fanatisme baginya akan
mempersempit pengetahuan seseorang, membuat seseorang tidak merdeka serta
menjadikan pola pikir seseorang menjadi tumpul. Di situlah sebenarnya awal
mula tertutupnya seseorang dari kebenaran.
Pada kenyataannya Murtaḍá sendiri telah melakukan yang dilarangnya
yaitu berupa fanatisme terhadap sosok Imam Ali. Dalam buku “Epistemologi
Islam”, Murtaḍá secara tegas mengatakan bahwa segala hal yang keluar dari
Imam Ali adalah kebenaran dan dapat dijadikan suatu hujjah. Hal ini kemudian
membuat penulis berpikir bahwa dalam pemikiran Murtaḍá tentang kebenaran
terdapat kemungkinan bias fanatisme tersebut.
2. Saran
Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai sisi teori kebenaran yang
terdampak bias fanatisme Murtaḍá Muṭahharī terhadap tokoh seperti yang telah
dijelaskan pada kritik.
Para akademisi perlu mengkaji lebih dalam lagi mengenai teori
kebenaran Murtaḍá untuk mengembangkan lebih baik lagi. Di samping itu juga
perlu penelitian mengenai pengaruh teori kebenaran atau secara umum dampak
pemikiran Murtaḍá terhadap masyarakat Indonesia, mengingat pemikiran
Murtaḍá telah diajarkan di berbagai kampus dan buku bukunya telah tersebar di
berbagai penjuru Indonesia.
109
DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku
Al-Attas, Muhammad Naquib, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M.
Naquib al-Attas (Hamid Fahmy, dkk., terj.), (Bandung: Mizan, 2003).
Algar, Hamid, “Hidup dan Karya Murtaḍá Muṭahharī”, dalam Murtaḍá
Muṭahharī, Filsafat Hikmah (Tim Penerjemah Mizan, terj.), (Bandung:
Mizan, 2002).
Angles, Peter L., A Dictionary of Philosophy, (London: Harper & Row
Publishers, 1981).
Anshari, Endang Saifuddin, Ilmu Filsafat dan Agama, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,
1987).
Arif, Oesman, Dasar-Dasar Ilmu Filsafat Timur dan Barat, (Solo: Matakin,
2009).
Armstrong, Karen, Sejarah Tuhan: Kisah 4.000 Tahun Pencarian Tuhan dalam
Agama-Agama Manusia (Zaimul Am, terj.), (Bandung: Mizan, 2011).
Arnando, Nina, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005).
Asay, Jamin, The Primitivist Theory of Truth, (New york: Cambridge University
Press, 2013).
https://books.google.co.id/books?id=3VICAQAAQBAJ&pg=PA12&dq=
Theories+of+Truth&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi3z9K43I3iAhUIXis
KHYLpAXYQ6AEITDAG#v=onepage&q=Theories%20of%20Truth&f
=false.
Bagir, Haidar, “Suatu Pengantar Kepada Filsafat Islam Pasca Ibn Rusyd”, dalam
Murtaḍá Muṭahharī, Filsafat Hikmah (Tim Penerjemah Mizan, terj.),
(Bandung: Mizan, 2002).
..........., Murtaḍá Muṭahharī Sang Mujahid, (Bandung: Yayasan Muṭahharī,
1988).
Bagus, Loren, Kamus Populer Filsafat, (Jakarta: Gramedia, 1996).
Baiquni, Ahmad, & Bakhtiar, Azam, Epistemologi Tasawuf: Sebuah Pengantar,
(Bandung: Mizan, 2017).
Bakhtiar, Amsal, Filsafat Agama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
..........., Filsafat Ilmu, (Jakarta: Rajagrafindo Press, 2012).
Baqir, Haidar, Epistemologi Tasawuf: Sebuah Pengantar, (Bandung: Mizan,
2017).
..........., Membincang Metodologi Ayatullâh Murtaḍá Muṭahharī, (Yogyakarta:
UGM, 2004).
Berlen, Ringkasan Sejarah Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1979).
Bertens, K., Etika, (Jakarta: Gramedia, 2007).
..........., Filsafat Barat Kontemporer: Inggris-Jerman, (Jakarta: Gramedia, 2002).
110
..........., Kata Pengantar, dalam Aristoteles, Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab
Suci Etika (Embun Kenyowati, terj.), (Jakarta: Teraju, 2004).
..........., Ringkasan Sejarah Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 2011.
Biyanto, Filsafat Ilmu dan Ilmu Keislaman, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
Brophy, Peter, Narrative-based Practice, (New York: Rutledge, 2016).
Cohen, Jack dkk, (eds.), Marx and Engels Collected Works, vol. 5,
(United Kingdom: Lawrence and Wishart).
Daldiyono, Bagaimana Dokter Berpikir dan Bekerja, (Jakarta: Gramedia, 2006).
Descartes, René, Meditations on First Philosophy (Elizabeth S. Haldane, tran.),
(Sydney: Cambridge University Press, 1911).
Driyarkara, Karya Lengkap Driyarkara, (Jakarta: Kompas, 2006).
Dua, A. Sonny Keraf dan Mikhael, Ilmu Pengetahuan: Sebuat Tinjauan Filosofis
(Yogyakarta: Kanisius, 2010).
Esposito, Jhn L., The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic Word (Eva Y.
N., dkk, terj.), jilid. 4, (Bandung: Mizan, 2001).
Faqih, Mansour, Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2002).
Garvey, James 20 Karya Filsafat Terbesar (C.P Mulyatno Pr., terj.),
(Yogyakarta: Kanisius, 2010).
al-Ghazālī, al-Munqidh min al-Ḍalāl, (Bairūt: Dāru al-Kutub al-ʻIlmiyyah,
1988).
..........., Tahafut al-Falasifah (Ahmad Maimun, terj.), (Yogyakarta: Grup Relasi
Inti Media, 2015).
Hadiwijono, Harun, Sari Sejarah Filsafat Barat 2, (Yogyakarta: Kanisius,1989).
Hamdani, Filsafat Sains, (Bandung, Pustaka Setia, 2011)
Hamdi, Ahmad Zainul, Tujuh Filsuf Muslim: Pembuka Pintu Gerbang Filsafat
Barat Modern, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004).
Hamersma, Harry, Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern, (Jakarta: Gramedia,
1992).
Harahap, Syahrin, Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam, (Jakarta: Istiqamah
Mulya Press, 2006).
Hardiman, F. Budi, Filsafat Modern: Dari Machiavaelli Sampai Nietzsche,
(Jakarta: Gramedia, 2007).
Harjana, A.Mangun, Isme-isme dalam Etika dari A Sampai Z, (Yogyakarta:
Kanisius, 1996).
Hartoko, Dick, Kamus Populer Filsafat, (Jakarta: Rajawali, 1986).
Hasan, Abdillah, Tokoh Mashur Dunia Islam, (Surabaya: Jawara, 2004).
Higgins, Robert C.Solomon dan Kathleen M., Sejarah Filsafat (Saut Pasaribu,
terj.), (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya).
111
Islam, Dewan Ensiklopedi, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
1997).
Ismail, Sanusi, Filsafat Sejarah Wacana Tentang Kausalitas dan Kebebasan
dalam Kehidupan Kolektif, (Banda Aceh: ar- Raniry Press, 2012).
Istanti, Kun Zachrun, Metode Penelitian Filologi dan Penerapannya,
(Yogyakarta: Elmatera, 2010).
J. Sudarminta, Epistemologi Dasar, (Yogyakarta: Kanisius, 2002).
Junaedi, Mahfud, Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam, (Depok: Kencana,
2017).
Kamal, Zainun, Ibn Taymiyah Versus Para Filosof Polemik Logika, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2006).
Kartanegara, Mulyadhi, Nalar Religius; Memahami Hakikat Tuhan, Alam, dan
Manusia, (Jakarta: Erlangga, 2007).
Kartanegara, Mulyadi Pengantar Epistemologi Islam, (Bandung: Mizan, 2003).
..........., Nalar Religius, (Jakarta: Erlangga, 2007).
Keraf, A. Sonny, & Dua, Mikchael, Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan
Filosofis, (Yogyakarta: Kanisius, 2010).
Khuza‟i, Rodliyah, Dialog Epistemologi Mohammad Iqbal Dan Charles S.
Peirce, (Bandung: Refika Aditama, 2007).
Kirkham, Richard L., Theories of Truth, (Cambridge: Massachusetts Institute of
Technology Press (MIT Press), 1992).
Labib, Muhsin, Filosof Sebelum dan Sesudah Mulla Shadra, (Jakarta: Lentera,
2005).
..........., Pemikiran Filsafat M.T Miṣbāḥ Yazdī, (Jakarta: Sadra Press, 2011).
Latif, Mukhtar Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu, (Jakarta: Prenada
Media Group, 2016).
Lubis, Akhyar Yusuf, Filsafat Ilmu: Klasik Hingga Kontemporer, (Depok:
Rajawali Press, 2016).
..........., Paradigma Positivisme dalam Epistemologi Pasca Positivisme, dalam
Heraty Noerhadi (ed.), Berpijak Kepada Filsafat: Kumpulan Sinopsis
Disertasi Program Pascasarjana Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan
Budaya Universitas Indonesia, (Depok: Komunitas Bambu, 2013).
M. Solihin, Perkembangan Pemikiran Filsafat Dari Klasik Hingga Modern
(Bandung: Pustaka Setia, 2007).
Magee, Bryan, The Story of Philosophy, Penerjemah Marcus Widodo dan
Hardono Hadi (Yogyakarta: Kanisius, 2012).
Manzhur, Ibnu, Lisān al-‘ Arab, (Beirut: Dār Shādir, 1412/1992).
Marsaoly, M. Said, “Memotret Muṭahharī Lebih Dekat: Sebuah Biografi”,
pengantar dalam Murtaḍá Muṭahharī, Mengapa Kita Diciptakan
(Mustamin Al Mandary, terj.), (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute,
2013).
112
Martineau, Harri, The Positive Philosophy of Auguste Comte, (Kitchener:
Batoche Books, 2000).
Mishbah, Yazdi, M.T., Iman Semesta (Ahmad Marzuki Amin, terj.), (Jakarta: al-
Huda, 2005).
Muchsin, Misri A., Filsafat Sejarah dalam Islam Landasan Konsepsi dan
Prospektif, (Banda Aceh: ar-Raniry Press 2005).
Muṭahharī, Murtaḍá, Bedah Tuntas Fitrah. Mengenal Jati Diri, Hakikat dan
Potensi Kita, (Jakarta : Citra, 2011).
..........., Belajar Konsep Logika: Menggali Struktur Berpikir ke Arah Konsep
Filsafat (Ibrahim Husein Al-Habsyi, terj.), (Yogyakarta: Rausyanfikr
Institute, 2013).
..........., Ceraman-Ceramah Seputar Persoalan Penting Agama dan Kehidupan
(Ahmad Subandi, terj.), (Jakarta: Lentera Basritama, 2000).
..........., Falsafath Kenabian (Ahsin Muhahham, terj.), (Jakarta: Pustaka Hidayah.
1991).
..........., Filsafat Agama dan Kemanusiaan (Arif Maulawi, terj.), (Yogyakarta:
Rausyanfikr, 2013).
..........., Filsafat Hikmah: Pengantar Kepada Pemikiran Sadra (Tim Penerjemah
Mizan terj.), (Bandung: Mizan, 2002).
..........., Filsafat Moral Islam: Kritik atas Berbagai Pandangan Moral
(Muhammad Babul Ulum dan Edi Hendri M, terj.), (Jakarta: al-Huda,
2004).
..........., Fitrah: Menyingkap Hakikat Potensi dan Jati Diri Manusia (H. Afif
Muhammad, terj.), (Jakarta: Lentera, 2008).
..........., Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam (Muhammad Abdul
Mun’im al-Khaqani, terj.), (Bandung: Mizan, 2009).
..........., Kenabian Terakhir (Muhammad Jawad Bafaqih, terj.), (Jakarta: Lentera,
2001).
..........., Kritik Islam terhadap Materialisme (Akmal Kamil, terj), (Jakarta: al-
Huda Islamic Centre, 2005).
..........., Manusia dan Alam Semesta: Konsep Islam tentang Jagat Raya (Haidar
Bagir, terj.), (Bandung: Mizan, 2007).
..........., Manusia Sempurna: Pandangan Islam Tentang Hakikat Manusia (M.
Hashem, terj.), (Jakarta: Lentera, 2001).
..........., Mengenal Epistemologi: Sebuah Pembuktian Terhadap Rapuhnya
Pemikiran Asing dan Kokohnya Pemikiran Islam (M.J. Bafaqih, terj.),
(Jakarta: Lentera, 2001).
..........., Mutiara Wahyu (Syekh Ali al-Hamid, terj.), (Bogor: Cahaya, 2004).
..........., Neraca Kebenaran Dan Kebatilan: Menjelajah Alam Pikiran Islam
(Najib Husain Alydrus, terj.), (Bogor: IPABI, 2001).
..........., Pengantar Epistemologi Islam, (Jakarta: Shadra Press, 2010).
113
..........., Pengantar Filsafat Islam: Filsafat Teoritis dan Filsafat Praktis (M.
Ilyas, terj.), (Yogyakarta: Rausyanfikr, 2003).
..........., Pengantar Ilmu-Ilmu Islam (Ibrahim Husein Al-Habsy, terj.), (Jakarta:
Pustaka Zahra, 2003).
..........., Tema-tema Pokok Nahj al-Balaghah (Arif Mulyadi, terj.), (Jakarta:
Islamic Center Jakarta, 2002).
..........., Teologi dan Falsafah Hijab, (Yogyakarta: Rausyanfikr Institute, 2013).
..........., Teori Pengetahuan: Catatan Kritis Atas Berbagai Isu Epistemologis
(Muhammad Jawad Bafaqih, terj.), (Jakarta: Sadra Press, 2019).
Najaf, 'Ain, Qiyadatul 'Ulama wal Ummah, (Taheran: Hikmah, t. th).
Nasr, Sayyed Hossein, Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern (Luqman
Hakim, terj.), cet, ke-1 (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994).
..........., “Pengantar”, dalam Muhammad Husein Thabathaba‟i, Hikmah Islam
(Husein Anis Al-Habsy, Bandung: Mizan, 1993).
..........., Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam (Tim Penerjemah Mizan, terj.),
(Bandung: Mizan, 2003).
Nasution, Harun, Falsafat dan Mistisisme dalam Islam, (Jakarta: Bulan bintang,
2008).
..........., Filsafat Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).
Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011).
Nur, Muḥammad, Murtaḍá Muṭahharī Kritik atas Moralitas Barat, (Kendal:
Penelitian Kompetitif Individual, 2016).
Pals, Daniel L, Seven Theories of Religion, (New York: Oxford University
Press, 1996).
Penerbit Marja, “Tentang Penulis”, dalam Murtaḍá Muṭahharī, ‘Ali Bin Abi
Thalib; Kekuatan dan Kesempurnaannya, (Zulfikar Ali, Bandung:
Penerbit Marja, 2005).
Poerwantana Dkk, Seluk-Beluk Filsafat Islam, (Bandung, PT Remaja
Rosdakarya, 1994).
Qardhawi, Yusuf, al-Ghazâlî antara Pro dan Kontra (Hasan Abrori, terj.),
(Surabaya: Pustaka Progressif, 1996).
Raeper, Linda Smith & William, Ide-Ide Filsafat dan Agama, Dulu dan
Sekarang, (Yogyakarta: Kanisius; 2004).
Rakhmat, Jalaluddin, “Murtaḍá Muṭahharī; Sebuah Model Buat „Ulama”, dalam
Murtaḍá Muṭahharī, Manusia dan Agama (Haidar Bagir, Bandung:
Mizan, 1995.
..........., Kata Pengantar dalam Murtaḍá Muṭahharī, Perspektif al-Qur’an
tentang Manusia dan Agama, (Bandung: Mizan, 1992).
Rapar, Jan Hendrik, Pengantara Filsafat, cet. ke-14, (Yogyakarta: Kanisius,
2010).
114
Richard, Teori-Teori Kebenaran (M. Khozim, terj.), (Bandung: Nusa Media,
2013).
Runes, Bagobert D, Dictionary of Philosophy, (Tottawa New Jersey: Adam‟s &
Co, 1971).
Russel, Bertrand, Sejarah Filsafat Barat (Wajiz Anwar, terj.), (Yogyakarta:
Yayasan al-Jami‟ah, 1968).
..........., Fakta, Kepercayaan, Kebenaran dan Pengetahuan, dalam buku Ilmu
dalam Perspektif (Jujun S. Suriasumantri, terj.), (Jakarta: Yayasan Obor,
2009).
Saleh, Editor A. Khudari, Pemikiran Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Jendela,
2003).
Shadr, Sayyid Muhammad Baqir Ash, Falsafatuna (M. Nur mufid bin Ali, terj.),
(Bandung: Mizan, 1995).
Snijders, Adelbert, Manusia dan Kebenaran: Sebuah Filsafat Pengetahuan,
(Yogyakarta: Kanisius, 2010).
Soleh, A. Khudori, Wacana Baru Filsafat Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004).
..........., Filsafat Islam: Dari Klasik Hingga Kontemporer, (Yogjakarta: Ar-
Rusyd Media, 2016).
Soyomukti, Nurani, Pengantar Filsafat Umum: dari Pendekatan Historis,
Pemetaan Cabang-Cabang Filsafat, Pertarungan Pemikiran, Memahami
Filsafat Cinta, hingga Panduan Berpikir Kritisi Filosofis, (Jogjakarta:
ar-Ruzz Media, 2016).
Subroto, Edi, Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural (Solo: LPP dan
UPT Penerbit dan Pencetakan UNS, 2007).
Sugiarto, Eko, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Kripsi dan Tesis
(Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 8. Diakses dari
https://books.google.co.id/books?id=jWjvDQAAQBAJ&printsec=frontc
over&dq=penelitian+kualitatif+adalah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjb
hf6AwJHdAhVJOY8KHQvBA5gQ6AEINDAB#v=onepage&q=peneliti
an%20kualitatif%20adalah&f=false.
Suhartono, Suparlan, Filsafat Ilmu Pengetahuan: Persoalan Eksistensi dan
Hakikat Ilmu Pengetahuan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008).
Sumantri, Jujun S. Suria, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 2014).
..........., Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat
Ilmu, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).
Susanto, A., Filsafat Ilmu: Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis,
Epistemologis dan Aksiologis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
Suseno, Franz Magnis, Dalam Bayang-Bayang Lenin: Enam Pemikiran
Marxisme Dari Lenin Sampai Tan Malaka, (Jakarta: Gramedia, 2016).
Syarif, MM., Para Filosof Muslim, (Bandung: Mizan, 1996).
115
Ṭabáṭabáī dan Muṭahharī, Murtaḍá, Menapak Jalan Spiritual. Penerjemah M.S
Nasrullah, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).
Tafsir, Ahmad, Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
Tim Penyusun Kamus PPPB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai
Pustaka, 1994).
Tjahjadi, Simon Petrus L., Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para
Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern, (Yogyakarta:
Kanisius; 2008).
Verhaak, C., & Iman, Haryono, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Telaah Atas Cara
Kerja Ilmu-ilmu, (Jakarta: Gramedia, 1989).
Wibisono, Koento, Arti Perkembangan menurut Positivisme Comte,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996).
Wijaya, Eko, Evolusi Kebudayaan Menurut Richard Dawkins, dalam Toeti
Heraty Noerhadi (ed.), Berpijak Kepada Filsafat: Kumpulan Sinopsis
Disertasi Program Pascasarjana Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan
Budaya Universitas Indonesia, (Depok: Komunitas Bambu, 2013).
Zachrie, Ridwan dan Wijayanto, Korupsi mengorupsi Indonesia: sebab, akibat,
dan prospek pemberantasan, (Bandung: Gramedia, 2013).Aidit, D. N.,
Tentang Marxisme, (Jakarta: Akademi Ilmu Sosial Aliarcham,
1962).
Zahra, Tim Pustaka, Biografi Murtaḍá Muṭahharī, dalam Murtaḍá Muṭahharī,
Pengantar Ilmu-Ilmu Islam (Ibrahim Husein al Habsyi, dkk., terj.),
(Jakarta: Pustaka Zahra, 2003).
Zamrulkhan, Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer, (Jakarta: Raja
Grafindo, 2016).
Referensi Jurnal Ilmiah
Arifin, Mochammad, “Epistemologi Rasionalisme Rene Descartes Dan
Relevansinya Terhadap Penafsiran al-Qur`An”, dalam Ilmu Ushuluddin,
vol.17, no. 2, Juli-Desember 2018.
Atabik, Ahmad, “Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu: Sebuah Kerangka
Untuk Memahami Konstruksi Pengetahuan Agama”, dalam Jurnal
Fikrah, Vol. 2, No. 1, Juni 2014.
Aziz, Ichwan Supandi, "Karl Raimund Popper dan Auguste Comte (Suatu
Tinjauan Tematik Problem Epistemologi dan Metodologi)”, dalam Jurnal
Filsafat, no. 3, Desember 2003.
Burhanuddin, Nunu, “Pemikiran Epistemologi Barat: dari Plati Sampai
Gonseth”, dalam Jurnal Intizar, vol. 21, no. 1, Januari 2015.
Chabibi, Muhammad, “Hukum Tiga Tahap Auguste Comte dan Kontribusinya
terhadap Kajian Sosiologi Dakwah”, dalam Nalar, vol. 3, no. 1, Juni
2019.
116
Dawson, Neal V., “Correspondence and Coherence in Science: A Brief
Historical Perspective”, in Jurnal Judgment and Decision Making, vol. 4,
no. 2, March 2009. Diakses dari http://journal.sjdm.org/ccdg/ccdg.html.
Diakses pada tanggal 01 Agustus 2019.
Dewi, Ernita, “Meretas Makna Kebenaran Dalam Diskursus Filosofis”, dalam
Substantia, vol. 12, no. 1, April 2010.
Dunwoody, Philip T., “Theories of Truth as Assessment Criteria in Judgment
and Decision Making”, dalam jurnal Judgment and Decision Making,
Vol. 4, No. 2, March 2009.
Farihah, Irzum, “Filsafat Materialisme Karl Marx: Epistemologi
Dialectical and Historical Materialism”, dalam Fikrah, vol. 3, no.
2, Desember 2015.
Fikri, Mursyid, “Rasionalisme Descartes dan Implikasinya Terhadap Pemikiran
Pembaharuan Islam Muhammad Abduh”, dalam Tarbawi, vo. 3, no. 2,
Juli-Desember 2018.
Gercke, J. W., dkk., “Philosophical Theories of Truth and The Logical Status of
Intra-Biblical Fallacies of Contextomy”, dalam Jurnal In die Skriflig,
Vol. 43, No. 4, 2009.
Hartono, Rudhy, “Ilmu dan Epistemologi”, dalam Jurnal Al-Huda, vol. III. vo. 9,
2003,
Hasan, Amin, “Menyusuri Hakikat Kebenaran: Kajian Epistemologi atas Konsep
Intuisi dalam Tasawuf al-Ghazali”, dalam Jurnal At-Ta‟dib, vol. 7, no. 2,
Desember 2012.
Hasanah, Ulfatun, “Kontribusi Pemikiran Auguste Comte (Positivisme) terhadap
Dasar Pengembangan Ilmu Dakwah”, dalam Al-I‟lam, vol. 2, no 2,
Maret 2019.
Henry, Chris, “The Politics of (Post) Truth: Theories of Truth in Contemporary
Philosophy”. Diakses dari
https://www.cumberlandlodge.ac.uk/sites/default/files/public/The%20Po
litics%20of%20%28Post%29%20Truth%20-
%20Philosophy%20Resources.pdf
Herafa, Beniharmoni, “Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum”, dalam
Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 2, No. 1, Februari 2016.
Inwansyah, Dedi, "Resonansi Pemikiran Pemimpin Islam Syiah Dalam Dunia
Pendidikan Indonesia: Studi Tentang SMA Plus Mutahhari”, dalam
Akademika, vol. 19, no. 01, Januari-Juni 2014.
Irawan MN, Aguk, “Filsafat Pragmatisme-Kontemporer: Ikhtiar Awal
Memahami Teori Charles Sanders Peirce”, vol.10, no.1, September
2013.
Ja‟far, Muhammad, “Pandangan Muṭahharī Tentang Agama, Sejarah, Al Quran
dan Muhammad”, dalam Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam Al-Huda, Vol.
III. No. 11. 2005.
117
James, William, “Pragmatism: A New Name For Some Old Ways Of Thinking”,
February, 2013. Diakses dari
https://www.gutenberg.org/files/5116/5116-h/5116-
h.htm#link2H_4_0008
Kamiana, Kadek Agus dkk, “Pengembangan Augmented Reality Book Sebagai
Media Pembelajaran Virus Berbasis Android”, dalam Karmapati, vol. 8,
no. 2, 2019.
Khaeroni, Cahaya, “Epistemologi Rasionalisme Rene Descarte Dan
Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam”, dalam Didaktika Religia, vol.
2, no. 2 Tahun 2014.
Labib, Muhsin, “Hawzah Ilmiyah Qom; Ladang Peternakan Filosof Muslim
Benua Lain”, dalam Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Islam Al-Huda, Vol. III.
No.9. 2003.
Laksono, Nur Idam, “Tasawuf untuk Kemanusiaan: Kajian terhadap Konsep
Fitrah Murtaḍá Muṭahharī”, dalam Attanwir, v. 05, no. 02, September
2015.
Luthfiyah, “Kritik Modernitas Menuju Pencerahan: Perspektif Teori Kritis
Mazhab Frankfurt”, dalam Tajdid, vol. 2, no. 1, April 2018, h. 281-282.
Maiaweng, Peniel, “Manfaat Kebenaran Perbuatan: Suatu Analisis Terhadap
Ajaran Filsafat Pragmatisme”, dalam Jurnal Researchgate, April 2013.
Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/318056102
Muchammad Abrori, Book Review dari buku “Matematikawan Muslim
Terkemuka” oleh Mohaini Mohamed, dalam Jurnal Kaunia, Vol. IV, No.
2 Oktober 2008.
Mustakim, “Pragmatisme dalam Filsafat Kontemporer: Analisa atas pemikiran
Charles S. Peirce”, dalam Jurnal al-Mabsut, Vol. 3, No. 1, 2012.
Nihaya, “Sinergitas Filsafat dan Teologi Murtaḍá Muṭahharī”, dalam Sulesana,
vol. 8. no 1, 2013.
Nugroho, Irham, “Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis dan Nilai
Etisnya Terhadap Sains”, dalam Cakrawala, vol. xi, no. 2, Desember
2016.
Nur, Muḥammad, Murtaḍá Muṭahharī Kritik atas Konsep Moralitas Barat,
dalam Didaktika Islamika, vol. 8, no. 2, Agustus 2016.
Nurdin, Fauziah, “Kebenaran Menurut Pragmatisme dan Tanggapannya
Terhadap Islam”, dalam Jurnal Islam Futura, Vol. 13. No. 2, Februari
2014.
Okulu, Elmadağ Polis Meslek Yüksek, “Karl Marx and Ralf Dahrendorf:
A Comparative Perspective on Class Formation and Conflict”,
dalam Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Iibf Dergisi, Agustus
2014.
Ormerod, R, “The History and Ideas of Pragmatism”, in Journal of the
Operational Research Society, Vol. 57, No. 8, 2006.
118
Rifai, Afga Sidiq, “Kebenaran Dan Keraguan Dalam Studi Keislaman”, dalam
The Journal of Religious Research (JPA), vol. 20, no. 1, Januari - Juni
2019.
Sabara, “Pemikiran Tasawuf Murtaḍá: Relasi Dan Kesatuan Antara
Intelektualitas, Spiritualitas dan Moralitas”, dalam al-Fikr, vol. 20, no. 1,
2016.
Salafudin, “Islamisasi Ilmu Pengetahuan”, dalam Jurnal Forum
Tarbiyah, Vol. 11, No. 2, Desember 2013.
Shahb, Maryam Shamsaei and Mohd Hazim, “Philosophical Study on Two
Contemporary Iranian Muslim Intellectual Responses to Modern Science
and Technology”, dalam International Journal Of Environmental &
Science Education, vol. 12, no. 4, 2017.
Shamsaei, Maryam, “Two Iranian Intellectuals: Ayatollah Morteza Motahari and
Dr. Abdol-Karim Soroush and Islamic Democracy Debate”, dalam IOSR
Journal of Humanities and Social Science, vol. 1, no. 2, 2012.
Somantri, Emma Dysmala, “Epistemologi Hukum Islam Rasional–Empirik”,
dalam Wawasan Hukum, vol. 26, no. 01, Februari 2012.
Supadjar, Ahmad Maliki dan Damardjadi, "Manusia dalam Eksistensialisme
Murtaḍá Muthadha Muṭahharī”, dalam Humanika, v. 18, no. 1, Januari
2005.
Suppe, Frederick, “Facts An Empirical Truth”, dalam Canadian Journal
of Philoshophy, Vol. iii, No. 2, Desember 1973.
Zubair, Achmad Charris, Filsafat Ilmu Menurut Konsep Islam, dalam Jurnal
Filsafat UGM, Maret 1997, h. 39. Diakses pada tanggal 04 September
2019 dari https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/download/31650/19181
Referensi Majalah
Beik, Abdullah, “Murtaḍá Muṭahharī; Muslim dalam Aqidah, Syari‟ah dan
Akhlaq”, dalam majalah Al-Isyraq No.4/Th.I, Jumadhil Akhir-Rajab,
1417 H
Rastan, Sastan, “Syahid Murtaḍá Muṭahharī; Pembangkit Kebangunan
Intelektual Islam”, dalam majalah Yaum Al-Quds, No. 9, Ramadhan
1403.
Referansi Makalah dan Karya Tulis Ilmiah
Endut, Mohd Shaiful Ramze, “Ali Shari‟ati and Morteza Motahhari‟s Ideological
Influences on Intellectual Discourse and Activism in Indonesia”, dalam
International Proceedings “Asian Public Intelectuals”, 2009/2010, h.
212. Diakses pada 12 oktober 2019 dari http://www.api-
fellowships.org/body/international_ws_proceedings/09/P5-Mohd.pdf
Iksan, Muchamad, Epistemologi Mencari Kebenaran Dengan Pendekatan
Transendental, Prosiding Seminar Nasional, ISBN 978-602-72446-0-3.
119
Sitorus, Fitzerald Kennedy, “RasionalismeRené Descartes: Saya Berpikir, Maka
Saya Ada”. Makalah disampaikan dalam Kelas Filsafat Filsafat Modern
Di Serambi Salihara, Sabtu, 12 November 2016.
Syamsuri, “Manusia Sempurna Perspektif Murtaḍá Muṭahharī”, Laporan
Penelitian Dosen, (Ciputat: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat,
Universitas Islam Negeri Jakarta, 2001).
Referensi Dari Situs Terpercaya
Fakhruddin Faiz, Teori Kebenaran, video youtube ke-1 menit ke 25.48, 17
Desember 2015. Diakses pada 19 Juli 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=hCNvfg_4P-o
http://journal-sport-q.lautan.info/id4/800-685/Euklides_22880_stikom-
bali_journal-sport-q-lautan.html
120
GLOSARI
Fakta : Sesuatu yang dengan dirinya ia bernilai sebagai
fakta atau kenyataan.
Fakta eksternal : Fakta yang terlepas dari mental manusia. Contohnya
bumi, langit, bintang, matahari, bulan, mendung dll.
Fakta internal : Fakta yang berada di dalam mental seseorang,
seperti pengetahuan-pengetahuan yang sudah pasti
seperti lingkaran, segi empat dll.
Koherensi : Teori kebenaran yang menjadikan idea sebagai tolok
ukur.
Korespondensi : Teori kebenaran yang menjadikan realitas (biasanya
memahami realitas sebagai realitas empiris) sebagai
tolok ukur.
Materi : Suatu yang meliputi benda-benda alam atau segala
yang dapat ditangkap oleh indra.
Muhmal : Suatu kata yang tak menunjukkan arti apa pun.
Pembawa kebenaran : Hal-hal yang bisa mempunyai nilai kebenaran, yaitu
hal macam apa yang bisa benar atau salah, seperti
proposisi, kalimat atau apa pun yang dipandang
sebagai pembawa kebenaran.
Qadhiyah : Kalimat sempurna dan mempunyai bermakna atau
arti tertentu yang jika kita verifikasi akan tampak
salah dan benarnya.
Qaul : Kata yang merujuk kepada suatu arti tertentu.
Rasionalisasi
: Ketidakbenaran yang kemudian diberikan alasan-
alasan rasional sehingga ia tampak seakan-akan
benar.
Tersibak
: Tersingkapnya tabir jiwa sehingga tidak ada lagi
halangan untuk mencapai kebenaran hakiki.
Pengertian Awwali : Pengertian dasar
121
INDEKS
A
Abstraksi 79
Aristoteles 5, 6, 7, 11, 25, 28, 32, 34,
41, 48, 56, 64, 88
Ayatullah Boroujerdi 55, 56, 58
Ayatullah Ruhani 58
B
Barat 6, 8, 14, 18, 19, 23, 34, 35, 37,
47, 49, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75,
89, 91, 104, 106, 112
Berpikir 6, 34, 49, 76
Bertrand Russel 19, 34, 49, 50, 52, 64,
89, 96
C
Charles S. Pierce 35, 36
D
Dimensi 23
E
Eksistensi 23, 42, 73, 81
Empiris 20, 108
Empirisme 20, 49
Euklides 34
F
Fanatisme 93, 94
Filsafat Praktis 73, 76, 78, 79, 80, 81,
82, 88, 89
Fitrah 2, 67, 72, 73, 75, 77, 78, 87, 91,
92
G
al-Ghazālī 6, 7, 9, 18, 38, 39, 40, 41
al-Qur‟an 75, 80, 93
H
Hati 20, 81, 91
Hikmah 65, 67, 85, 109
I
Ibnu Sīnā 6, 9, 16, 18, 41, 42, 43, 57,
62
Imāmiyah 55, 56
Irfan 56, 61, 67, 68, 85
Islam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 32,
35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72,
73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 109, 111
J
Jalan Spiritual 90, 91
K
Karl Marx 4, 8, 10, 14, 15, 80, 96, 97,
98, 99, 100, 102
Kebenaran 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15,
16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 47, 49, 50, 52, 53, 72, 73,
75, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87,
91, 92, 101, 102, 103, 104, 105,
107, 111
Kenyataan 10, 50, 108
Keraguan 103, 104
Kesadaran 72
Khomeini 56, 57, 58, 59, 60, 61
Koherensi 32, 88
Konsep 2, 6, 15, 16, 40, 42, 44, 66, 72,
74, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 92, 96
122
Korespondensi 28
Kritik 14, 19, 55, 63, 66, 82, 83, 86,
96, 103, 107, 108, 109, 111, 112
L
Logika 6, 7, 32, 35, 67, 68, 76, 77
M
Materialisme 45, 59, 73, 96
Metodologi 6, 17, 58, 108, 112
Mirza Mahdi Syahidi Razavi 55
Miṣbāḥ Yazdī 19, 46, 47, 61, 62
Murtaḍá Muṭahharī 2, 3, 4, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 41, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 96, 102, 103, 106, 107,
108, 109, 111
N
Naqīb al-„Aṭās 5, 19, 43, 44
Neptune 84
O
Objek 31, 46, 50, 83, 86, 88
P
Pemahaman 21, 22, 46, 77, 86
Pembawa Kebenaran 75
Pendekatan 18, 22, 34, 74
Pengalaman 20, 89
Pengetahuan3, 5, 8, 22, 23, 25, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 44, 46, 50, 52, 73,
81, 82, 107
Pernyataan 4, 31, 33, 40, 50, 75, 78,
89
Persesuaian 74
Plato 4, 5, 10, 23, 24, 32, 33, 37, 49,
80, 87
Proposisi afirmatif 85
Q
Qom 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67
R
Rasional 103
Realitas 73
S
Subjek 31, 46
T
Tasawuf 2, 27, 28, 40, 55, 68, 72, 85
Teori 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 22,
23, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 43, 45, 47, 51, 52, 53, 82,
84, 98, 100, 106, 107, 109, 112
Teori Kebenaran 12, 23, 28, 30, 31,
32, 33, 35, 51, 52
W
William James 35, 37