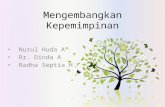STUDI LINTAS BUDAYA KEPEMIMPINAN GAYA KOREA DI ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of STUDI LINTAS BUDAYA KEPEMIMPINAN GAYA KOREA DI ...
STUDI LINTAS BUDAYA
KEPEMIMPINAN GAYA KOREA DI INDONESIA
Pada PT. Semarang Garment
Tesis
Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Pascasarjana
pada program Magister Manajemen Pascasarjana
Universitas Diponegoro
Disusun oleh :
NDARU RISDANTI, ST
NIM. 12010111400165
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013
iii
PENGESAHAN TESIS
Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis berjudul :
STUDI LINTAS BUDAYA
KEPEMIMPINAN GAYA KOREA DI INDONESIA
Pada PT. Semarang Garment
yang disusun oleh Ndaru Risdanti, NIM 1201 0111 400 165
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Desember 2013
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.
Pembimbing Utama Pembimbing Anggota
Dr. Suharnomo, Msi Dr. Edy Rahardja, Msi
Semarang, 20 Desember 2013
Universitas Diponegoro
Program Pascasarjana
Program Studi Magister Manajemen
Ketua Program
Dr. Sugeng Wahyudi, MM
iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“ The seat of knowledge is in the head,
the seat of wisdom is in the heart”
-William Hazlitt-
“Seberapa keras kita berusaha, kita tidak akan
pernah bisa „membeli‟ waktu. Yang bisa kita lakukan
hanyalah menggunakan waktu secara bijaksana”
-Napoleon Hiell-
Persembahan
Bapak dan almarhumah Ibu tercinta yang selalu menginspirasi, senantiasa
memberi dorongan, doa dan kasih sayangnya
Kakak dan adik tersayang
Teman dan sahabat tersayang
v
ABSTRACT
The aim of this research is to investigate the Korean style of leadership in
Indonesia at one of the multi national companies in Indonesia. This kind of cross
cultural study need to be barried by the dimensions of national culture. In order to
get depht information about Korean Style of Leadership, there are six dimensions
of Kluchkhon & Strodtbeck’s concept and five dimensions of Parson’s theory
about national culture used in this research.
The objects of this study are the employees at a multinatonal company in
Semarang which consist of the expatriates manager from Korea and local
employees from Indonesia.
The result of this research shows the Korean managers’s style of
leadership in one of multi national companies from Korea located in Semarang,
Indonesia. Korean style of leadership in Indonesia include some dimensions of
how they see about nature of human, focus responsibility, relation to broad
environment, activity, time, space, afective or afective neutrality, universalim or
particularism, ascription or achievment, specify or not, and self oriented or
collective oriented.
Keywords: cross cultural study, leadership, Korean style leadership.
vi
ABSTRAKSI
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai kepemimpinan
gaya Korea di Indonesia pada salah satu perusahan multi nasional di Indonesia.
Penelitian lintas budaya ini sebaiknya dibatasi oleh beberapa dimensi terkait
budaya nasional. Untuk memperoleh kedalaman informasi mengenai
kepemimpinan gaya Korea, terdapat enam dimensi dari konsep Kluchkhon dan
Strodtbeck serta lima dimensi dari pola-pola Parson yang digunakan dalam
penelitian ini.
Objek pada penelitian ini adalah karyawan pada sebuah perusahaan multi
nasional di Semarang yang terdiri dari manajer ekspatriat dari Korea dan
karyawan lokal dari Indonesia.
Hasi peneletian ini menunjukkan kepemimpinan sesuai dengan gaya
manajer Korea pada perusahaan multi nasional yang berlokasi di Semarang
dimana mencakup dimensi mengenai bagaimana mereka melihat karakter dasar
manusia, fokus tanggung jawab, hubungannya dengan lingkungan, aktivitas,
waktu, ruang, afektif atau netralitas afektif, universalisme atau partikularisme,
askripsi atau prestasi, spesifitas atau kekaburan dan orientasi diri atau orientasi
kolektif.
Kata kunci : studi lintas budaya, kepemimpinan, kepemimpinan gaya korea.
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq
serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis mengenai “Studi
Lintas Budaya, Kepemimpinan Gaya Korea di Indonesia”.
Adapun maksud dari penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan studi pada Program Pasca Sarjana Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Tesis ini dapat terselesaikan dengan
bantuan serta dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin
mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1. Bapak Dr.Sugeng Wahyudi, MM, selaku Direktur Program Studi Magister
Manajemen Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr. Suharnomo, MSi, selaku dosen pembimbing I yang telah
meluangkan waktu dan memberikan pengarahan, saran serta dukungan dalam
penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Dr. Edy Rahardja, MSi, selaku dosen pembimbing II yang telah
meluangkan waktu dan memberikan pengarahan, saran serta dukungan dalam
penyelesaian tesis ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Manajemen Fakultas
Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Bapak dan Almarhumah Ibu yang selalu memberikan doa, dukungan, fasilitas,
serta kasih sayang yang luar biasa hingga terselesaikannya tesis ini.
viii
6. Kakak dan adik yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam
penyelesaian tesis ini.
7. Tri Jatmniningsih, ST, teman baik yang memberikan bantuan dalam
penyelesaian tesis ini.
8. Renni, Ares, Wirda, Bila, Latifah, Dea dan Nisa yang selalu mendukung
dalam semangat dan doa sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Teman-teman Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro
angkatan 40 pagi yang telah berbagi cerita dan kebersamaan.
10. Seluruh staf karyawan Program Studi Magister Manajemen Fakultas
Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak
membantu penulis selama proses perkuliahan serta penyusunan tesis.
Penulis menyadari akan kekurangsempurnaan penulisan tesis ini. Oleh
sebab itu segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis
harapkan agar kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.
Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak
yang membacanya.
Semarang, Desember 2013
Penulis,
Ndaru Risdanti, ST
ix
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul ............................................................................................... i
Surat Pernyataan Keaslian Tesis .................................................................. ii
Halaman Persetujuan/Pengesahan ............................................................... iii
Halaman Motto/Persembahan ...................................................................... iv
Abstract ........................................................................................................... v
Abstraksi ......................................................................................................... vi
Kata Pengantar .............................................................................................. vii
Daftar Isi ......................................................................................................... ix
Daftar Tabel .................................................................................................... xii
Daftar Gambar ............................................................................................... xiii
BAB I Pendahuluan .................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................... 1
1.2 Perumusan Masalah ....................................................................... 9
1.3 Tujuan Penelitian .......................................................................... 11
1.4 Kegunaan Penelitian....................................................................... 11
BAB II Tinjauan Pustaka .......................................................................... 12
2.1 Landasan Teori .............................................................................. 12
2.1.1 Kepemimpinan ...................................................................... 12
2.1.2 Beberapa Teori Kepemimpinan ............................................ 15
2.1.3 Gaya Kepemimpinan ............................................................. 21
2.1.4 Pemahaman Budaya .............................................................. 22
2.1.4.1 Budaya ...................................................................... 22
2.1.4.2 Budaya Nasional ....................................................... 26
2.1.4.3 Dimensi Keragaman Kultural ................................... 28
2.1.5 Kebudayaan Indonesia .......................................................... 40
x
2.1.6 Kebudayaan Korea ................................................................ 42
2.2 Penelitian Terdahulu ...................................................................... 47
2.3 Kerangka Pikir ............................................................................... 49
BAB III Metode Penelitian ......................................................................... 51
3.1 Pendekatan Penelitian .................................................................... 51
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ................................ 52
3.2.1 Variabel Penelitian .............................................................. 52
3.2.2 Definisi Operasional ............................................................ 52
3.3 Penentuan Populasi dan Sample .................................................... 59
3.3.1 Ukuran Populasi ................................................................... 59
3.3.2 Sampel ................................................................................... 57
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel................................................. 58
3.4 Jenis dan Sumber Data .................................................................. 58
3.5 Metode Pengumpulan Data ........................................................... 59
3.6 Metode Analisis Data ..................................................................... 62
3.7 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan ..................................................... 69
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan ............................................... 71
4.1 Hasil Penelitian .............................................................................. 71
4.1.1 Gambaran Umum PT. Semarang Garment .......................... 71
4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan ............................................ 72
4.1.3 Lokasi Perusahaan ................................................................. 76
4.1.4 Aktivitas dalam PT. Semarang Garment ............................... 76
4.2 Pembahasan .................................................................................... 86
4.2.1.Profil Responden ................................................................... 87
4.2.2 Analisis dan Keabsahan Data ............................................... 87
4.2.3 Persepsi Manajer dari Korea dan Karyawan Lokal............... 88
4.2.4 Karakteristik Kepemimpinan Lintas Budaya Berdasarkan
Kluchkhon dan Strodtbeck serta Pola-pola Parson ............... 92
BAB V Kesimpulan .................................................................................... 105
5.1 Kesimpulan .................................................................................... 105
xi
5.2 Implikasi Kebijakan ....................................................................... 107
5.3 Keterbatasan Penelitian ................................................................. 111
5.4 Agenda Penelitian Mendatang ....................................................... 112
Daftar Pustaka
Lampiran
xii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Cultural Orientation and Dimensions ...................................... 36
Tabel 4.1 Daftar Responden / Nara sumber ............................................. 87
Tabel 4.2 Hasil Analisis ........................................................................... 106
xiii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir ........................................................................ 49
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Semarang Garment ............................ 73
Gambar 4.2 Proses Produksi PT. Semarang Garment ................................. 77
Gambar 4.3 Beberapa Kegiatan Produksi PT. Semarang Garment ............. 78
Gambar 4.4 Beberapa Kegiatan Pelatihan PT. Semarang Garment ............. 80
Gambar 4.5 Kegiatan Lain PT. Semarang Garment .................................... 81
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada awal tahun 2000 istilah Hallyu atau Korean Wave menjadi populer di
kawasan Asia Timur yang disebabkan oleh meledaknya musik pop dan serial
drama Korea. Istilah Korean Wave pertama kali muncul di Cina pada tahun 1997
melalui serial drama Korea yang ditayangkan di televisi nasional China. Korean
wave atau Hallyu adalah proses penyebaran nilai dan budaya popular Korea
Selatan ke seluruh dunia. Produk-produk Korean Wave yang populer adalah serial
drama TV, musik K-Pop, film, game dan fashion. Korea Selatan melalui film dan
musik, berusaha untuk menyebarkan citra baru yang positif mengenai negaranya
dan memperkenalkan budayanya ke seluruh dunia. Strategi tersebut dapat
dikatakan berhasil. Beberapa film dan serial drama Korea Selatan sukses di pasar
internasional. Dampak dari kesuksesan ini terlihat pada pertumbuhan ekonomi
dan pariwisata di Korea Selatan. Industri budaya memberi konstribusi terhadap
GDP Korea Selatan yang terus meningkat. Pada tahun 2000, industri budaya
memberikan konstribusi sebesar 3,6 % terhadap GDP Korea Selatan dan pada
tahun 2010 terjadi peningkatan yaitu 6,5 % dari total GDP.
Korean Wave merupakan salah satu contoh kesuksesan sebuah negara
dalam mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan secara maksimal untuk
mendukung pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran negara. Korea Selatan
melalui Korean Wave secara bertahap mampu membangun citra positif Korea
2
Selatan di mata dunia internasional serta memberikan konstribusi terhadap
pendapatan nasional.
Kemajuan Korea Selatan tidak hanya ditunjukkan dengan citra budaya
positif yang mampu menembus seluruh penjuru dunia. Pembangunan yang cepat
terjadi di dalam negeri Korea begitu juga dalam dunia perekonomian dan bisnis.
Salah satu kekuatan ekonomi Korea Selatan digerakkan oleh sistem jaringan. Bila
bangsa China menggunakan akar jaringan rantau yang berbasis pada klan/marga,
dialek, lokalitas, perhimpunan dan terpenting kepercayaan. Bangsa Korea juga
menerapkan akar jaringan yang sama yakni kepercayaan yang lebih dikenal
dengan Chaebol. Jaringan Chaebol Korea merupakan konglomerasi korporasi
raksasa yang menguasai ekonomi Korea. Chaebol didukung oleh keluarga, namun
berbeda dengan Keiretsu di Jepang atau Grupo di Amerika Latin, para pemimpin
Chaebol hampir tidak pernah memegang posisi resmi/legal chaebol yang
dipegangnya. Diantara konglomerasi Chaebol adalah korporasi raksasa Samsung,
LG, Hyundai-Kia dan SK.
Selama empat dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang
menakjubkan telah menjadi bagian dari apa yang dijuluki sebagai ”Keajaiban di
Kawasan Asia Timur.” Korea Selatan akan mengambil posisi yang lebih positif
dengan visi yang lebih luas serta melaksanakan diplomasi global melalui
kerjasama secara aktif dengan masyarakat internasional.
Era globalisasi yang terjadi pada dunia internasional saat ini tidak hanya
membawa keterbukaan sebuah negara terhadap budaya negara lain, tetapi juga
memunculkan berbagai konsekuensi dalam setiap aspek kehidupan manusia,
termasuk dalam bidang bisnis dengan seluruh komponen yang mendukung bidang
3
tersebut. Saat ini para pimpinan bisnis dalam rangka mengelola organisasi
perusahaannya memerlukan visi dan perspektif internasional jika mereka
berkeinginan mencapai sukses dan memajukan perusahaannya. Tidak terkecuali
bagi para pelaku bisnis di Korea Selatan. Kesuksesan organisasi sangat ditentukan
oleh kemampuan pimpinan perusahaan untuk beradaptasi dalam lingkungan
internasional yang lebih luas, sangat dinamis, serta penuh dengan peluang dan
tantangan. Beberapa perusahaan besar di dalam negeri Korea Selatan telah
memperluas usahanya dengan membuka perusahaan-perusahaan yang
ditempatkan di luar negerinya (Multi National Corporation / MNC).
Sehubungan dengan arus globalisasi, berbagai strategi akan dilakukan oleh
perusahaan yang memiliki jangkauan operasi di berbagai negara atau lebih dikenal
dengan Multi Nasional Corporation (MNC). Strategi yang dilakukan oleh
perusahaan multi-nasionional, khususnya di Korea Selatan yakni dengan
meningkatkan daya saing produk yang mereka hasilkan, memberikan pengetahuan
tentang lingkungan internasional, mengamati strategi bersaing yang dilakukan
oleh para pesaing mereka, hingga perubahan kebijakan yang dilakukan terhadap
penilaian prestasi atau kinerja bagi seorang calon manajer yang akan
dipromosikan untuk menjalani penugasan luar negeri terlebih dahulu (expatriates)
agar mereka mampu dan memiliki pengalaman yang lebih luas dengan kondisi
lingkungan domestik pekerjaan yang mereka tekuni. Keberhasilan mereka
mengemban penugasan tersebut menjadi penilaian prestasi mereka untuk jabatan
yang lebih tinggi (promosi). Penugasan internasional menjadi semakin penting
saat ini dan telah menjadi bagian dari karir para manajer (managerial career).
4
Sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut maka kompetensi kepemimpinan lintas
budaya sangat diperlukan dalam perusahaan yang beroperasi secara internasional.
Secara lebih nyata kondisi ini akan sangat mempengaruhi interaksi antara
manajer yang ditugaskan ke luar negeri (expatriates manager) dengan para
karyawan lokal mereka, yang kenyataannya sangat memerlukan berbagai tingkat
adaptasi dari pihak manajer maupun karyawan lokal mereka. Bagi para manajer,
hal tersebut sangat erat berhubungan dengan gaya kepemimpinan yang harus
diterapkan akibat dari perbedaan budaya yang mereka miliki. Demikian juga bagi
karyawan lokal mereka yang harus menerima dan menyesuaikan perilaku dengan
manajer dari luar negaranya. Keberhasilan dalam penyesuaian dari kedua belah
pihak merupakan kunci sukses bagi kinerja organisasi secara keseluruhan. Bagi
para manajer yang ditugaskan di luar negeri (expatriates manajer) tantangan
tersebut terasa lebih berat dan memiliki konsekuensi besar jika dibandingkan
dengan kondisi yang harus dialami para karyawan. Hal ini disebabkan oleh posisi
mereka sebagai pimpinan yang harus mampu mempengaruhi para karyawan agar
mereka bersedia untuk bekerjasama dalam melaksanakan operasional perusahaan,
dimana keberhasilan para manajer akan dievaluasi dan ditentukan bagi jenjang
karir mereka selanjutnya. Berbagai tantangan akan muncul bagi para manajer
yang ditugaskan di luar negeri (expatriates manajer), terutama yang berasal dari
kekuatan sosial budaya yang diwakili oleh perbedaan budaya baik budaya
nasional (negara) yang bersangkutan maupun perbedaan budaya organisasi yang
berlaku dalam menjalankan bisnis mereka.
Menurut Korea Chamber of Commerce and Indutry, di Indonesia saat ini
terdapat sekitar 1400 perusahaan Korea yang aktif beroperasi. Mulai dari
5
perusahaan global kelas dunia seperti Samsung, LG, Hyundai, sampai perusahaan
menengah dan kecil. Perusahaan Korea di Indonesia memperkerjakan sekitar
500,000 tenaga kerja di Indonesia, mulai dari level direktur, manager hingga ke
level karyawan biasa. Jumlah warga Korea yang menetap di Indonesia pun cukup
banyak yakni kurang lebih 30,000 orang. Perusahaan Korea berhasil
membuktikan dirinya sejajar dengan perusahaan kelas dunia lainnya. Produk
buatan Korea, khususnya elektronik dapat ditemukan di setiap rumah tangga di
seluruh dunia. Bahkan beberapa brand Korea telah mengalahkan brand Jepang
yang lebih dulu hadir dan menguasai pasar dunia, contohnya Samsung yang telah
menggeser dominasi Sony ataupun LG yang cukup dominan di Indonesia.
Perusahaan Korea dipengaruhi oleh kultur confusian yang kental.
Perusahaan Korea umumnya memiliki sistem hirarkhi yang tinggi dan
terdesentralisasi dalam beberapa orang key people termasuk para manager yang
bisa membuat keputusan. Deskripsi kerja, kewenanangan, dan hubungan kerja
antara atasan dan bawahan didasari oleh senioritas. Walaupun cukup banyak
orang Korea yang mengikuti pendidikan di luar negerinya, norma-norma sosial
Confusian masih dominan. Karekter perusahaan multinasional Korea tidak jauh
berbeda dengan perusahaan Jepang. Mereka mengutamakan kerja tim,
memperhatikan sikap atau prilaku dan sangat disiplin. Pada umumnya di
perusahaan multinasional Korea yang lebih muda atau junior amat menghormati
senior atau orang yang berumur lebih tua sehingga akan menjadi suatu hal yang
tabu jika melawan kata-kata dari orang yang lebih tua.
Budaya suatu masyarakat tercermin dalam cara hidup kelompok suatu
masyarakat, yang dapat diamati melalui manifestasinya, seperti pandangan
6
terhadap waktu, keluarga, kebiasaan berdagang (berbisnis) dan sebagainya. Haris
dan Morgan (1987, dalam Czinkota) menginventarisir elemen-elemen budaya
antara lain bahasa, kepercayaan, nilai dan sikap, perilaku dan kebiasaan,
keindahan, pendidikan dan sosial institusi. Budaya bertindak sebagai sumber
eksternal yang mempengaruhi perilaku karyawan pada kepribadian sehari-harinya
yang akibatnya mempengaruhi perilaku setiap orang dalam organisasi, karena
setiap orang membawa sepotong dunia luar ke tempat kerja. Secara keseluruhan,
dampak budaya masing-masing individu menciptakan perubahan dalam budaya
dari organisasi itu sendiri. (Trace and Bayer dalam Keyong, 2010). Memahami
nilai-nilai budaya penting untuk dimiliki anggota organisasi agar mampu
mengidentifikasi, memahami dan merespon perbedaan dalam berpikir, merasa dan
bertindak anggota organisasi lain dengan latar belakang budaya yang berbeda.
Bagi perusahaan multi nasional, pengetahuan budaya dan sensitivitas nilai-nilai
budaya adalah sebuah kebutuhan yang harus ditangani pada praktek manajemen
dan pelatihan. Perbedaan budaya nasional para manajer dalam suatu perusahaan
dengan karyawannya menciptakan keberagaman budaya dalam perusahaan.
Keberagaman ini akan membawa ikatan budaya yang melekat pada suatu
masyarakat berbeda dengan budaya yang melekat pada masyarakat lain. Dapat
kita ambil kesimpulan bahwa telah terjadi akulturasi budaya. Akulturasi adalah
proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan
tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing yang
berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur asing tersebut lambat laun
diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri (Koentjaraningrat, 1980).
7
Keberhasilan sistem manajemen sangat tergantung pada kemampuan
kepemimpinan yang dimiliki oleh pimpinan dan manajer dalam perusahaan yang
bersangkutan (leadership competence). Lebih jauh, keberhasilan kepemimpinan
tersebut akan sangat teruji dalam lingkungan asing atau internasional, hal ini
disebabkan karena dalam lingkungan tersebut akan terjadi perubahan terhadap
kekuatan eksternal yang akan mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak
langsung pada kekuatan internal perusahaan. Sangat diperlukan kepemimpinan
yang efektif untuk perusahaan-persuahaan yang memiliki karyawan dari berbagai
latar belakang budaya nasional yang berbeda. Kepemimpinan itu sendiri akan
memiliki berbagai macam dampak antara lain kepuasan pengikut atau bawahan.
Untuk melihat lebih jauh mengenai kepemimpinan manajer dengan latar belakang
budaya Korea Selatan terhadap karyawan yang merupakan penduduk lokal
Indonesia akan dibatasi dengan dimensi-dimensi dari kerangka budaya
Kluckhohn dan Strodtbeck. Keenam dimensi tersebut nantinya akan digunakan
untuk menganalisis kepemimpinan gaya Korea yang diterapkan jajaran manajer
dengan latar belakang budaya nasional korea dan bagaimana penerimaan
masyarakat lokal (berkebudayaan Indonesia) terhadap kepemimpinan budaya
korea tersebut di Indonesia. Dengan adanya keragaman budaya dalam perusahaan
tersebut maka dibutuhkan analisis terhadap jajaran manajer ekspatriat
berkebangsaan Korea dan para karyawan lokal pada PT. Semarang Garment.
Perusahaan Multi Nasional PT. Semarang Garment adalah salah satu
perusahaan yang merupakan perluasan perusahaan Kukdong Corporation yang
berpusat di Seoul, Korea Selatan. Perusahaan tersebut dipimpin langsung oleh
seorang pimpinan berkewarganegaraan Korea yang bernama Byun Hyo Su
8
dengan jajaran manajer yang berkebangsaan Korea dan sejumlah karyawan lokal
dari Indonesia. Di dalam perusahaan tersebut pasti terjadi interaksi kepemimpinan
lintas budaya yang nyata antara manajer asing (expatriates manager) dan
bawahan lokal mereka.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hofstede, ciri budaya nasional
Korea Selatan antara lain 1) Korea Selatan yang menganggap beberapa orang
lebih superior dibandingkan dengan yang lain karena status sosial, gender, ras,
umur, pendidikan, kelahiran, pencapaian, latar belakang dan lainnya 2) Korea
Selatan yang cenderung menjunjung tinggi konformitas dan keamanan 3) Orang
Korea Selatan lebih suka menghindari risiko 4) Orang Korea Selatan selalu
mengikuti peraturan formal dan juga ritual yang berlaku di Korea Selatan 5) di
Korea Selatan, kepercayaan hanyalah diberikan kepada keluarga dan teman yang
terdekat 6) Masyarakat Korea Selatan menerima hubungan kekuasaan yang lebih
autokratik dan patrenalistik, bawahan mengenal kekuasaan orang lain melalui
formalitas, misalnya posisi hierarki. Kriteria budaya nasional Korea Selatan yang
demikian akan berbeda dengan budaya nasional Indonesia meskipun beberapa
dimensi budaya antar dua negara tersebut memiliki persamaan karena berada pada
payung besar budaya yang sama, yaitu budaya Asia.
Atas dasar itulah peneliti tertarik untuk mengambil tema penelitian
mengenai cross cultural leadership, khususnya kepemimpinan gaya Korea di
Indonesia yang mengambil obyek penelitian pada PT. Semarang Garment.
9
1.2 Rumusan Masalah
Kepemimpinan lintas budaya terjadi pada perusahaan multinasional yang
memperluas usahanya ke luar negeri. Pada PT. Semarang Garment terjadi
interaksi yang nyata antara jajaran manajer dengan latar belakang budaya Korea
Selatan dan karyawan yang berbudaya lokal Indonesia. Perbedaan budaya Korea
Selatan dan budaya Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek dalam perilaku
individu khususnya dalam suatu organisasi perusahaan. Perbedaan budaya
nasional dalam suatu perusahaan menimbulkan beberapa dampak dalam
organisasi perusahaan dikarenakan karakter individu yang terbentuk dari budaya
nasional masing-masing negara juga berbeda. Perbedaan manajemen Korea dan
Indonesia menjadi suatu masalah yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dengan
adanya perbedaan budaya nasional antara pimpinan atau manajer yang
berkebudayaan Korea dengan karyawan yang berkebudayaan Indonesia perlu
adanya suatu proses adaptasi dari kedua belah pihak dan proses kepemimpinan
lintas budaya yang efektif.
Dalam hal ini, keenam dimensi Kluckhohn & Strodtbeck dan pola-pola
Parson yang digunakan untuk menganalisis kepemimpinan jajaran manajer
dengan latar belakang budaya nasional Korea Selatan pada perusahaan dengan
karyawan berpenduduk lokal dengan budaya nasional Indonesia di PT. Semarang
Garment. Selain itu dapat dilihat bagaimana karyawan lokal berbudaya Indonesia
menerima kepemimpinan dengan gaya Korea di lingkungan kerjanya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa pertanyaan
penelitian sebagai fokus dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
10
1. Bagaimana kepemimpinan gaya Korea ditinjau dari dimensi hubungannya
terhadap alam, orientasi waktu, sifat dasar manusia, orientasi aktivitas, fokus
aktivitas, dan konsepsi ruang sesuai dengan kerangka budaya Kluckhohn dan
Strodtbeck, serta dimensi afektivitas-netralitas afektif, universalisme-
partikularisme, ketersebaran-keterkhususan, askripsi-prestasi, orientasi
instrumental-ekspresif sesuai dengan pola-pola Parson yang diterapkan oleh
jajaran manajer ekspatriat berkebudayaan Korea Selatan di Indonesia pada
PT. Semarang Garment?
2. Bagaimana penerimaan karyawan lokal berbudaya Indonesia terhadap gaya
kempemimpinan gaya Korea yang diterapkan pada PT. Semarang Garment?
Mengacu kepada identifikasi di atas, maka fokus penelitian dapat dibatasi
pada kepemimpinan gaya Korea jajaran manajer di PT. Semarang Garment yang
merupakan manajer ekspatriat dari Korea Selatan terhadap karyawan lokal
berkebudayaan Indonesia di dalam perusahaan tersebut.
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka
tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis kepemimpinan gaya Korea
terhadap karyawan lokal berkebangsaan Indonesia di PT. Semarang Garment
Indonesia yang dibatasi dengan enam dimensi budaya dari Kluchkohn dan
Strodtbeck serta lima dimensi dari pola-pola Parson.
11
1.4. Kegunaan Penelitian
1. Bagi sosok pemimpin
Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan dan arahan bagi seorang
pemimpin dalam menerapkan gaya kepemimpinan lintas budaya yang efektif
dalam perusahaan multi nasional.
2. Bagi pihak perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu dasar
pertimbangan dalam menentukan langkah dan kebijakan perusahaan multi
nasional.
3. Bagi peneliti lain
Diharapkan bisa dijadikan acuan dan pengetahuan untuk penelitian-penelitian
di bidang sumber daya manusia terutama yang berkenaan dengan
kepemimpinan lintas budaya.
4. Bagi masyarakat
Penelitian ini diharapkan membuka wawasan masyarakat perihal pentingnya
kepemimpinan lintas budaya yang efektif dalam memajukan sebuah
organisasi serta menambah pengetahuan masyarakat perihal kepemimpinan
gaya Korea di Indonesia.
5. Bagi peneliti
Dalam penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui lebih mendalam
gaya kepemimpinan lintas budaya seorang tokoh dan pemimpin sebuah
perusahaan multi nasional, khususnya perusahaan Korea di Indonesia.
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1 Kepemimpinan
Kepemimpinan merupakan tema yang popular, tanpa adanya pemimpin
para karyawan tidak akan dapat bekerja dengan baik, karena fungsi pemimpin di
sini diperlukan untuk mempengaruhi, memotivasi karyawan serta ikut serta dalam
proses pengambilan keputusan. Manajemen seringkali disamakan dengan
kepemimpinan. Abraham Zaleznik (dalam Robbins, 2002) misalnya, berpendapat
bahwa pemimpin dan manajemen sangat berbeda. Mereka berbeda dalam
motivasi, sejarah pribadi, dan cara berpikir serta bertindak. Zaleznik mengatakan
bahwa manajer cenderung mengambil sikap impersonal dan pasif terhadap tujuan,
sedangkan pemimpin mengambil sikap pribadi dan aktif terhadap tujuan.
Sedangkan Kotter (dalam Robbins, 2002) menganggap baik kepemimpinan dan
manajemen sama pentingnya bagi keefektifan organisasional yang optimal.
Namun ia yakin bahwa kebanyakan organisasi kurang dipimpin (underled) dan
terlalu ditata-olah (overmanaged). Munandar (2001) melihat kepemimpinan
sendiri lebih berhubungan dengan efektivitas sedangkan manajemen lebih
berhubungan dengan efisiensi. Kepemimpinan merupakan sesuatu yang penting
bagi manajer. Para manajer merupakan pemimpin (dalam organisasi mereka),
sebaliknya pemimpin tidak perlu menjadi manajer. Jadi definisi kepimimpinan
secara luas menurut Robbins (2002) yaitu sebagai kemampuan untuk
mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Menurut Siagian
13
(1995) kepemimpinan merupakan keterampilan dan kemampuan seseorang untuk
mempengaruhi orang lain, melalui komunikasi baik langsung, maupun tidak
langsung dengan maksud untuk menggerakan orang-orang tersebut agar dengan
penuh pengertian dan kesadaran bersedia mengikuti kehendak-kehendak
pemimpin tersebut. Menurut Stoner, et al (1995) kepemimpinan didefinisikan
sebagai proses pengarahan dan memepengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan
tugas dari para anggota kelompok. Berdasarkan uraian tentang definisi
kepemimpinan di atas, menurut Nitisemito, 2001 (dalam Marcian, 2008) dapat
disimpulkan bahwa unsur kunci kepemimpinan adalah pengaruh yang dimiliki
seseorang dan akibat pengaruh itu bagi orang yang hendak dipengaruhi.
Kemampuan mempengaruhi adalah yang dominan dari kepemimpinan, dan
keberhasilan seorang pemimpin adalah bagaimana ia bisa memotivasi dan
menginspirasi orang lain. Teori-teori kepemimpinan dengan demikian dapat
diterapkan pada manajer. Dalam hal ini manajemen dapat kita anggap sebagai
kepemimpinan dalam perusahaan. Menurut Munandar (2001) kepemimpinan
merupakan pengertian yang meliputi segala macam situasi yang dinamis, yang
berisi:
a. Seorang manajer sebagai pemimpin yang mempunyai wewenang untuk
memimpin.
b. Bawahan yang dipimpin, yang membantu manajer sesuai dengan tugas
mereka masing-masing.
c. Tujuan atau sasaran yang harus dicapai oleh manajer bersama-sama dengan
bawahannya.
14
Efektifitas kepemimpinan biasanya dipertimbangkan dari segi tercapainya
suatu tujuan. Orang memandang kepemimpinan itu efektif atau tidak efektif dari
segi kepuasan yang diperoleh dari pengalaman pekerjaan seluruhnya. Penerimaan
dari pengarahan atau perintah seorang pemimpin sebagian besar tergantung dari
harapan para bawahannya, apabila mereka menanggapinya secara baik, maka akan
mendapatkan hasil yang menarik. Pemimpin yang baik harus memiliki empat
macam kualitas yaitu kejujuran, pandangan ke depan, mengilhami pengikutnya,
dan kompeten. Pemimpin yang tidak jujur tidak akan dipercaya dan akhirnya tidak
mendapat dukungan dari pengikutnya. Pemimpin yang memiliki pandangan ke
depan adalah pemimpin yang memiliki ke depan lebih baik. Pemimpin yang baik
juga harus mampu mengilhami pengikutnya dengan penuh antusiasme dan
optimisme. Pemimpin yang baik juga harus memiliki kompetensi dalam
menjalankan tugas secara efektif, mengerti kekuatannya, dan menjadi pembelajar
terus-menerus (Tampubolon, 2007). Selain itu, pemimpin yang efektif adalah
yang (1) bersikap luwes, (2) sadar mengenai diri, kelompok, dan situasi, (3)
memberi tahu bawahan tentang setiap persoalan dan bagaimana pemimpin pandai
dan bijak menggunakan wewenangnya, (4) mahir menggunakan pengawasan
umum di mana bawahan tersebut mampu menyelesaikan pekerjaan dalam batas
waktu yang ditentukan, (5) selalu ingat masalah mendesak, baik keefektifan
jangka panjang secara individual maupun kelompok sebelum bertindak, (6)
memastikan bahwa keputuan yang dibuat sesuai dan tepat waktu baik secara
individu maupun kelompok, (7) selalu mudah ditemukan bila bawahan ingin
membicarakan masalah dan pemimpin menunjukan minat dalam setiap
gagasannya, (8) menepati janji yang diberikan kepada bawahan, cepat menangani
15
keluhan, dan memberikan jawaban secara sungguh-sungguh dan tidak berbelit-
belit serta (9) memberikan petunjuk dan jalan keluar tentang metode/mekanisme
pekerjaan dengan cukup, meningkatkan keamanan dan menghindari kesalahan
seminimal mungkin.
2.1.2 Beberapa Teori Kepemimpinan
Bila berbicara mengenai kepemimpinan, maka terlebih dahulu harus
membahas teori-teori kepemimpinan. Robbins (1996) membagi teori mengenai
kepemimpinan ke dalam empat kategori, yaitu :
1. Teori Ciri Kepemimpinan (The Leadership Characteristic theory)
Teori Ciri Kepemimpinan adalah teori yang mencari ciri kepribadian,
sosial, fisik, atau intelektual yang memperbedakan pemimpin dari bukan
pemimpin. Dalam teori ini diidentifikasikan ciri-ciri yang dikaitkan secara
konsisten dengan kepemimpinan yaitu enam ciri yang cenderung membedakan
pemimpin dari bukan pemimpin adalah ambisi dan energi, hasrat untuk
memimpin, kejujuran dan integritas (keutuhan), percaya diri, kecerdasan, dan
pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Di samping itu, riset baru-baru ini
memberikan bukti kuat bahwa orang-orang yang mempunyai sifat pemantauan
diri yang tinggi artinya sangat luwes dalam menyesuaikan perilaku mereka dalam
situasi yang berlainan, jauh lebih besar kemungkinannya untuk muncul sebagai
pemimpin dalam kelompok-kelompok ketimbang yang pemantauan dirinya
rendah.
16
2. Teori Perilaku Kepemimpinan (Behavioral Theories of Leadership)
Teori Perilaku Kepemimpinan adalah teori-teori yang mengemukakan
bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Adapun
teori-teori yang termasuk ke dalam Teori Perilaku Kepemimpinan adalah:
a. Studi-studi Kepemimpinan Ohio State
Menurut Yukl (1994) kuesioner penelitian tentang perilaku kepemimpinan
yang efektif telah didominasi oleh pengaruh dari kepemimpinan dari Ohio
State University. Sebuah sasaran utama untuk mengidentifikasi perilaku
kepemimpinan yang efektif. Analisis faktor dari jawaban kuesioner memberi
indikasi bahwa para bawahan memandang perilaku atasannya pertama-tama
dalam kaitannya dengan dua dimensi atau kategori arti dari perilaku, yang
kemudian disebut sebagai “consideration” dan “initiating structure”.
Kedua-duanya adalah kategori yang didefinisikan secara luas yang terdiri
atas sejumlah varietas yang luas mengenai jenis-jenis perilaku yang spesifik.
Consideration adalah tingkat sejauh mana seorang pemimpin bertindak
dengan cara ramah dan mendukung, memperlihatkan perhatian terhadap
bawahan, dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Contohnya termasuk
melakukan kebaikan kepada bawahan, mempunyai waktu untuk
mendengarkan masalah para bawahan, mendukung atau berjuang untuk
seorang bawahan, berkonsultasi dengan bawahan mengenai hal yang penting
sebelum dilaksanakan, bersedia untuk menerima saran dari bawahan, dan
memperlakukan bawahan sebagai sesamanya.
Initiating structure (struktur memprakarasai) adalah tingkat sejauh mana
seorang pemimpin menentukan dan menstruktur perannya sendiri dan peran
17
dari para bawahan kearah pencapaian tujuan-tujuan formal kelompok.
Contohnya termasuk memberi kritik kepada pekerjaan yang jelek,
menekankan pentingnya memenuhi batas waktu, menugaskan bawahan,
mempertahankan standar-standar kinerja tertentu, meminta bawahan untuk
mengikuti prosedur-prosedur standar, menawarkan pendekatan baru terhadap
masalah, mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan, dan memastikan bahwa
bawahan bekerja sesuai dengan batas kemampuannya.
b. Telaah Universitas Michigan
Telaah kepemimpinan yang dilakukan pada Pusat Survei dan Survei
Universitas Michigan mempunyai riset yang serupa dengan riset yang
dilakukan di Ohio yaitu melokasi karakteristik perilaku pemimpin yang
tampaknya dikaitkan dengan ukuran keefektifan kinerja. Kelompok Michigan
juga membagi perilaku pemimpin ke dalam dua dimensi yaitu pemimpin
berorientasi karyawan dan pemimpin berorientasi produksi. Pemimpin yang
berorientasi karyawan (employee oriented leader) menekankan pada hubungan
antarpribadi, memberikan perhatian pribadi terhadap kebutuhan karyawan
dam menerima perbedaan individual di antara para anggota. Sebaliknya
pemimpin yang berorientasi produksi (production oriented leader) cenderung
menekankan aspek teknis atau tugas dari pekerjaan tertentu, perhatian utama
mereka adalah pada penyelesaian tugas kelompok mereka, dan anggota-
anggota kelompok adalah suatu alat untuk tujuan akhir itu.
c. Kisi-kisi Manajerial Blake & Mouton dan Studi Skandinavia
Suatu penggambaran grafis dari pandangan dua dimensi terhadap gaya
kepemimpinan dikembangkan oleh Blake dan Mouton. Mereka
18
mengemukakan Kisi Manajerial berdasarkan gaya “kepedulian akan orang”
dan “kepedulian akan produksi”, yang pada hakikatnya mewakili dimensi
pertimbangan dan struktur prakarsa dari Ohio atau dimensi berorientasi
karyawan dan berorientasi produksi dari Michigan. Kisi manajerial itu sendiri
merupakan suatu matriks sembilan kali sembilan yang membagankan delapan
puluh satu gaya kepemimpinan yang berlainan.
Berdasarkan penemuan-penemuan Blake dan Mouton, para manajer
berkinerja paling baik pada gaya 9,9 dimana perhatiannya pada produksi
tinggi tetapi perhatiannya pada karyawan juga tinggi, jika dibandingkan
dengan gaya 9,1 (tipe otoritas) atau gaya 1,9 (tipe laissez-faire).
Studi skandinavia mengatakan premis dasar mereka adalah bahwa dalam
suatu dunia yang berubah, pemimpin yang efektif akan menampakkan
perilaku yang berorientasi pengembangan (orients expansion). Mereka adalah
para pemimpin yang menghargai eksperimentasi, mencari gagasan baru, serta
membuat dan mengimplementasikan perubahan.
3. Teori Kontingensi (Contingency Theory)
Teori Kontingensi merupakan pendekatan kepemimpinan yang mendorong
pemimpin memahami perilakunya sendiri. Teori ini mengatakan bahwa
keefektifan sebuah kepemimpinan adalah fungsi dari berbagai aspek situasi
kepemimpinan (Ivancevich, Konopaske, Matteson, 2007). Adapun lima teori yang
termasuk ke dalam teori kontingensi adalah :
a. Model kontingensi Fiedler (Fiedler Contingency Model)
Mengemukakakan bahwa kinerja kelompok yang efektif bergantung pada
padanan yang tepat antara gaya si pemimpin dan sampai tingkat mana situasi
19
memberikan kendali dan pengaruh kepada si pemimpin. Fiedler menciptakan
instrument, yang disebutnya LPC (Least Preffered Co-Worker) yang
bermaksud mengukur apakah seseorang itu berorientasi tugas atau hubungan.
Kemudian setelah gaya kepemimpinan dasar individu dinilai melalui LPC
yang bermaksud mengukur apakah seseorang itu berorientasi tugas ataukah
hubungan, Fiedler mendefinisikan faktor-faktor hubungan pemimpin-
anggota, struktur tugas dan kekuasaan jabatan sebagai faktor situasi utama
yang menentukan efekftivitas kepemimpinan.
b. Teori Situasional Hersey dan Blanchad
Merupakan suatu teori kemungkinan yang memusatkan perhatian pada para
pengikut. Kepemimpinan yang berhasil dicapai dengan memilih gaya
kepemimpinan yang tepat, yang menurut argument Hersey dan Blanchard
bersifat tergantung pada tingkat kesiapan atau kedewasaan para pengikutnya.
Tekanan pada pengikut dalam keefektifan kepemimpinan mencerminkan
kenyataan bahwa para pengikutlah yang menerima baik atau menolak
pemimpin. Tidak peduli apa yang dilakukan si pemimpin itu, keefektifan
bergantung pada tindakan dari pengikutnya. Inilah dimensi penting yang
kurang ditekankan dalam kebanyakan teori kepemimpinan. Istilah kesiapan,
seperti didefinisikan oleh Hersey dan Blanchard, merujuk ke sejauh mana
orang mempunyai kemampuan dan kesiapan untuk menyelesaikan suatu tugas
tertentu.
c. Teori Pertukaran Pemimpin-Anggota
Menurut teori ini para pemimpin menciptakan kelompok-dalam dan
kelompok-luar, dan bawahan dengan status kelompok-dalam akan
20
mempunyai penilaian kinerja yang lebih tinggi, tingkat keluarnya karyawan
yang lebih rendah, dan kepuasan yang lebih besar bersama atasan mereka.
Hal pokok yang harus dicatat di sini adalah bahwa walaupun pemimpinlah
yang melakukan pemilihan, karakteristik pengikutlah yang mendorong
keputusan kategorisasi dari pemimpin.
d. Teori Jalur-Tujuan Robert House (House’s Path Goal Theory)
Merupakan teori bahwa perilaku seorang pemimpin dapat diterima baik oleh
bawahan sejauh mereka pandang sebagai suatu sumber dari atau kepuasan
segera atau kepuasan masa depan. Hakikat teori ini adalah bahwa merupakan
tugas si pemimpin untuk membantu pengikutnya dalam mencapai tujuan
mereka dan untuk memberikan pengarahan yang perlu dan / atau dukungan
guna memastikan tujuan mereka sesuai dengan sasaran keseluruhan dari
kelompok atau organisasi.
e. Teori Model Partisipasi-Pemimpin Vroom dan Yetton
Merupakan suatu teori kepemimpinan yang memberikan seperangkat aturan
untuk menentukan ragam dan banyaknya pengambilan keputusan partisipatif
dalam situasi-situasi yang berlainan.
4. Teori Neo-Karismatik (Neocharismatic Theories)
Merupakan teori kepemimpinan yang menekankan simbolisme, daya tarik
emosional, dan komitmen pengikut yang luar biasa. Teori-teori yang termasuk ke
dalam teori ini adalah
a. Teori Kepemimpinan Karismatik (Charismatic Leadership)
Teori Kepemimpinan Karismatik mengemukakan bahwa para pengikut
membuat atribusi dari kemampuan kepemimpinan yang heroic atau luar biasa
21
bila mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. Kepemimpinan karismatik
mungkin tidak selalu diperlukan untuk mencapai tingkat kinerja karyawan
yang tinggi. Mungkin paling tepat bila tugas dari pengikut memiliki suatu
komponen ideologis atau bila lingkungan melibatkan satu tingkat stress dan
ketidakpastian yang tinggi.
b. Teori Kepemimpinan Transformasional
Teori yang menyatakan bahwa pemimpin memberikan pertimbangan dan
ransangan intelektual yang diindividualkan dan yang memiliki karisma.
c. Teori Kepemimpinan Transaksional
Merupakan teori yang menyatakan bahwa pemimpin memandu atau
memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan
memperjelas peran dan tuntutan tugas.
d. Teori Kepemimpinan Visioner (Visionary Leadership)
Teori dimana pemimpin memiliki kemampuan untuk menciptakan dan
mengkomunikasikan visi yang realistis, dapat dipercaya, dan menarik
mengenai masa depan bagi suatu organisasi atau unit organisasi, yang tumbuh
dan menjadi semakin baik di masa sekarang.
2.1.3 Gaya Kepemimpinan
Dalam mensukseskan kepemimpinan dalam organisasi, pemimpin perlu
memikirkan dan memperlihatkan gaya kepemimpinan yang akan diterapkan
kepada pegawainya (Mulyadi dan Rivai, 2009). Stoner, et al. (1995) memberikan
definisi tentang gaya kepemimpinan yaitu berbagai pola tingkah laku yang disukai
oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Paul
22
Hersey dan K. H Blanchard, 1982 (dalam Marcian 2008) menyebutkan gaya
kepemimpinan adalah pola perilaku yang dilakukan oleh seseorang pada waktu
tertentu dan berupaya mempengaruhi aktivitas orang lain. Menurut Umar (2004)
gaya kepemimpinan adalah suatu cara atau teknik seseorang dalam menjalankan
suatu kepemimpinan dan dapat pula diartikan sebagai norma perilaku yang
digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku
orang lain seperti yang ia lihat, dalam hal ini usaha menselaraskan persepsi
diantara orang yang akan mempengaruhi perilaku dengan yang akan dipengaruhi
menjadi amat penting. Gaya atau cara/norma perilaku yang dipergunakan oleh
sesorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain
seperti yang ia inginkan, menurut Miftah Thoha (1994), disebut gaya
kepemimpinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan
yaitu pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan pemimpin,
dengan menyatukan tujuan atau sasaran yang telah menjadi komitmen bersama
(Abdilah, 2011).
2.1.4 Pemahaman Budaya
2.1.4.1 Budaya
Setiap kelompok masyarakat tertentu akan mempunyai cara yang berbeda
dalam menjalani kehidupannya dengan sekelompok masyarakat yang lainnya.
Cara-cara menjalani kehidupan sekelompok masyarakat dapat
didefinisikansebagai budaya masyarakat tersebut. Satu definisi klasik mengenai
budaya adalah sebagai berikut: "budaya adalah seperangkat pola perilaku yang
secara sosial dialirkan secara simbolis melalui bahasa dan cara-cara lain pada
23
anggota dari masyarakat tertentu (Wallendorf & Reilly dalam Mowen, 1995). Di
lain sisi budaya menurut (Tyler dalam Mowen, 1995) merupakan “a complex
whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, customs, and any other
capabilities and habits acquired by man as a member of society”.
Ada pula definisi yang menyatakan bahwa budaya adalah pola utuh
prilaku manusia dan produk yang dihasilkannya yang membawa pola pikir, pola
lisan, pola aksi, dan artifak, dan sangat tergantung pada kemampuan seseorang
untuk belajar, untuk menyampaikan pengetahunnya kepada generasi berikutnya
melalui beragam alat, bahasa, dan pola nalar. Kedua definisi tersebut menyatakan
bahwa budaya merupakan suatu kesatuan utuh yang menyeluruh, bahwa budaya
memiliki beragam aspek dan perwujudan, serta bahwa budaya dipahami melalui
suatu proses belajar (Keyong, 2010)
Definisi di atas menunjukkan bahwa budaya merupakan cara menjalani
hidup dari suatu masyarakat yang ditransmisikan pada anggota masyarakatnya
dari generasi ke generasi berikutnya. Proses transmisi dari generasi ke generasi
tersebut dalam perjalanannya mengalami berbagai proses distorsi dan penetrasi
budaya lain. Hal ini dimungkinkan karena informasi dan mobilitas anggota suatu
masyarakat dengan anggota masyarakat yang lainnya mengalir tanpa hambatan.
Interaksi antar anggota masyarakat yang berbeda latar belakang budayanya
semakin intens. Oleh karena itu, dalam proses transmisi budaya dari generasi ke
generasi, proses adaptasi budaya lain sangat dimungkinkan. Misalnya proses
difusi budaya populer di Indonesia terjadi sepanjang waktu. Kita bisa melihat
bagaimana remaja-remaja di Indonesia meniru dan menjalani budaya populer dari
negara-negara Barat, sehingga budaya Indonesia sudah tidak lagi dijadikan dasar
24
dalam bersikap dan berperilaku. Proses seperti inilah yang disebut bahwa budaya
mengalami adaptasi dan penetrasi budaya lain. Dalam hal-hal tertentu adaptasi
budaya membawa kebaikan, tetapi di sisi lain proses adaptasi budaya luar
menunjukkan adanya rasa tidak percaya diri dari anggota masyarakat terhadap
budaya sendiri.
Agar budaya terus berkembang, proses adaptasi seperti dijelaskan di atas
terus perlu dilakukan. Paradigma yang berkembang adalah bahwa budaya itu
dinamis dan dapat merupakan hasil proses belajar, sehingga budaya suatu
masyarakat tidak hadir dengan sendirinya. Proses belajar dan mempelajari budaya
sendiri dalam suatu masyarakat disebut enkulturasi (enculturati). Enkulturasi
menyebabkan budaya masyarakat tertentu akan bergerak dinamis mengikuti
perkembangan zaman. Sebaliknya sebuah masyarakat yang cenderung sulit
menerima hal-hal baru dalam masyarakat dan cenderung mempertahankan budaya
lama yang sudah tidak relevan lagi disebut sebagai akulturasi (acculturation).
Budaya yang ada dalam sekelompok masyarakat merupakan seperangkat
aturan dan cara-cara hidup. Dengan adanya aturan dan cara hidup/ anggota
dituntun untuk menjalani kehidupan yang serasi. Masyarakat diperkenalkan pada
adanya baik-buruk, benar-salah dan adanya harapan-harapan hidup. Dengan
aturan seperti itu orang akan mempunyai pijakan bersikap dan bertindak. Jika
tindakan yang dilakukan memenuhi aturan yang telah digariskan, maka akan
timbul perasaan puas dalam dirinya dalam menjalani kehidupan. Rasa bahagia
akan juga dirasakan oleh anggota masyarakat jika dia mampu memenuhi
persyaratan-persyaratan sosialnya. Orang akan sangat bahagia jika mampu
bertindak baik menurut aturan budayanya. Oleh karena itu, budaya merupakan
25
sarana untuk memuaskan kebutuhan anggota masyarakatnya. Kebudayaan,
menurut (Soemardjan, 2010) adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.
Mengacu pendapat tersebut, maka karya masyarakat akan menghasilkan teknologi
dan kebudayaan yang berwujud benda, misalnya rumah, makanan, senjata,
pakaian dan sebagainya.
Budaya kerja biasanya didapatkan disekolah ketika kita remaja, sedangkan
budaya organisasi didapatkan pada tahap akhir setelah kita menjadi karyawan dari
sebuah perusahaan, biasanya pada saat dewasa. Dalam proses pembelajaran, nilai
dikembangkan lebih awal untuk memainkan peran dalam proses penyeleksian dan
nilai apa saja yang diterapkan (Frits, 2002). Menurut (Hofstede, 2005) budaya
dapat diterapkan dalam beberapa cara yaitu:
a. Symbols merupakan kata-kata, gambar, gerak tubuh atau objek yang
membawa arti tertentu, hanya diakui oleh mereka yang berbagi budaya. Kata-
kata dalam bahasa atau jargon termasuk dalam kategori ini. Simbol
dimasukkan ke dalam lapisan, terluar dangkal.
b. Heroes, mengacu pada manusia, kematian, kenyataan atau imajiner, memiliki
karakter yang mulia dan sangat dipuji dalam suatu budaya dan dengan
demikian menjadi teladan dalam budaya tersebut.
c. Rituals adalah kegiatan kolektif secara teknis berlebihan dalam mencapai
tujuan yang diinginkan, tetapi yang dalam suatu budaya, dianggap sebagai
sosial penting misalnya tata cara berbicara dan menghormati orang lain.
d. Value mengacu pada manifestasi terdalam, atau inti dari budaya. Nilai adalah
kecenderungan yang luas untuk memilih negara tertentu melebihi
26
kecenderungannya dengan negara lain. Mereka adalah hal pertama anak-anak
belajar tanpa disadari.
Dalam keanekaragaman budaya terjadi perbedaan karakter, nilai hidup, dll,
sehingga mengelola perbedaan merupakan hal penting galam berhubungan dengan
pihak lain. Mengelola perbedaan berarti memungkinkan semua karyawan untuk
mewujudkan potensi-potensinya secara maksimum. Hal itu menitikberatkan
kepada perubahan budaya dan infrastruktur organisasi sedemikian rupa sehingga
karyawan dapat memberikan hasil produktivitas karyawan yang maksimal. Dasar
pemikiran rasional untuk mengelola perbedaan terletak pada hasil legal, sosial,
dan moral. Secara sederhana, alasan utama untuk mengelola perbedaan adalah
kemampuan untuk membangun dan memelihara usaha dalam lingkungan yang
kompetitif. Hal ini menjelaskan bahwa pentingnya perusahaan untuk mengelola
perbedaan dengan pertama kali meninjau ulang trend demografi yang
menimbulkan adanya perbedaan diantara tenaga kerja. (Robert, 2005)
2.1.4.2 Budaya Nasional
Budaya nasional merupakan pedoman dasar bagi karyawan untuk
memahami pekerjaan, dan pendekatan untuk melakukan pekerjaan serta harapan
karyawan untuk diperlakukan. Budaya nasional memiliki arti bahwa suatu cara
bertindak tertentu lebih disukai karena dinggap cocok dengan nilai-nilai budaya
daripada yang lain. Bila praktek manajemen. Tidak sesuai dengan budaya nasional
yang telah dipercaya dan dianut, karyawan akan merasa tidak enak, tidak puas,
tidak berkomitmen dan tidak menyukai. Karyawan akan merasa tidak suka atau
terganggu bila diminta oleh manajemen untuk bertindak yang tidak sesuai dengan
nilai-nilai budayanya. (Mas’ud, 2002).
27
Budaya merupakan sesuatu yang seharusnya dipelajari dan bukan untuk
diwariskan (Hofstede, 2005). Nilai yang mendalam akan mewakili perasaan yang
luas mengenai kebaikan dan kejahatan, keindahan dan kejelekan, rasional dan
irrasional. Praktek yang diperkenalkan biasanya melalui manusia, misalnya
kebiasaan kolektif disajikan dalam sesuatu yang terlihat seperti pakaian, bahasa,
dan jargon, simbol status, kriteria promosi, tata cara pertemuan, gaya komunikasi,
dan banyak lagi. Nilai-nilai dan praktek baik milik perangkat lunak suatu budaya,
ada juga hardware dalam bentuk bangunan, perlatan kantor, dan jenis kendaraan
yang mencerminkan karakteristik budaya.
Budaya nasional memiliki komposisi tingkat nilai lebih tinggi
dibandingkan dengan tingkat prakteknya, sedangkan budaya organisasi memiliki
tingkat praktek yang lebih beragam dibandingkan tingkat nilainya. Budaya
nasional adalah program yang pertama yang tertanam kedalam diri kita, nilai
merupakan komponen terdalam dari program tersebut. Pada saat kita dewasa
biasanya nilai-nilai sudah tertanam dengan baik sehingga sulit berubah.
Sistem bangsa telah diperkenalakan diseluruh dunia pada pertengahan
abad ke duapuluh, diikuti dengan sistem kolonial yang telah dikembangkan tiga
abad sebelumnya. Dalam periode kolonial, kemajuan teknologi negaranegara
Eropa Barat yang hanya disebarkan pada negara-negara mereka saja, sehingga
mereka membagi seluruh territorial wilayah didunia yang tidak memiliki kekuatan
politik. Batas wilayah antara sebelum kolonial dan sesudah kolonial ditentukan
oleh para penguasa kolonial dibanding dengan penduduk setempat. Oleh karena
itu, bangsa tidak dapat disamakan dengan masyarakat hisoris. Bentuk-bentuk asli
yang telah dikembangkan organisasi sosial, sebenarnya merupakan konsep
28
kebudayaan umum yang berlaku untuk seluruh masyarakat, dan bukan untuk
bangsa. Namun, banyak negara yang keutuhan historisnya dikembangkan bahkan
bila dalam negara tersebut terdiri-dari kelompok yang berbeda, mereka akan
menjadi kelompok minoritas yang kurang terintergrasi. Dalam bangsa yang telah
ada selama beberapa waktu ada kekuatan yang kuat terhadap intergrasi secara
berkelanjutan. Hal ini bisa dalam bentuk bahasa nasional yang dominan, media
massa umum, sistem pendidikan nasional, tentara nasional, sistem politik
nasional, representasi nasional di acara olahraga dengan simbolis yang kuat dan
emosional.
2.1.4.3 Dimensi Keragaman Kultural untuk Mengkaji Perbedaan
Budaya
Perbedaan budaya di antara komunitas perusahaan inti dan komunitas
petani plasma dijelaskan dengan bertolak dari adanya pergulatan di antara dua
prinsip yang disebut sebagai perekonomian dualistik. Pergulatan ini berakar dari
pertentangan antara kapitalisme barat yang modern dan tradisi pra-kapitalis.
Kapitalisme barat yang modern, muda, dan agresif yang dibangun di kota besar
berhadapan dengan tradisi pra-kapitalis yang tua yang berada di pedesaan (Boeke,
1983:11).
Menurut Boeke (1983:11), dalam situasi dualistik terdapat dua
karakteristik yang berbeda dalam konteks sosial ekonomi. Satu sisi merupakan
golongan masyarakat yang memiliki ikatan sosial asli dan organis, sistem
kesukuan tradisional, kebutuhan yang sifatnya terbatas dan bersahaja, serta prinsip
produksi pertanian yang sifatnya subsisten. Sisi lainnya adalah masyarakat yang
berorientasi keuntungan, bersaing usaha yang terorganisasikan, profesional,
29
bertumpu pada kapitalisasi dan industri mekanis, serta memandang rendah
dorongan atau motif ekonomi yang dikaitkan dengan motif sosial, etika, adat,
tradisi, suku, agama, dan sebagainya. Dalam kehidupan pertanian, kapitalisme
diasosiasikan dengan farmer yang berciri kota, sementara prakapitalisme
diasosiasikan dengan peasant yang berciri desa.
Dalam kerangka ini peasant merupakan masyarakat yang (1) hidup dari
mengolah tanah, (2) hidup menetap dalam komunitas pedesaan, (3) menggunakan
teknologi pertanian, seperti pacul, bajak, dan garu untuk melakukan produksi
pertanian, (4) memiliki hubungan dengan kota. Selain itu juga mengolah tanah
untuk tujuan subsistensi.
Kroeber dalam Foster (1967:2) mengemukakan bahwa peasant merupakan
bagian masyarakat dari suatu budaya yang hidup dalam kaitannya dengan pasar
dan pusat kota. Golongan masyarakat ini tidak lagi terisolasi, namun masih
memegang nilai tradisional. Sementara itu menurut Firth (Marzali, 1998:85),
sistem ekonomi peasant adalah sistem ekonomi yang menggunakan ketrampilan
dan pembagian kerja sederhana, memiliki keterbatasan akses ke pasar, alat
produksi dikuasai dan diorganisasikan secara nonkapitalistik, skala produsen
tergolong kecil dengan hubungan produksi bersifat lebih personal, dan perhatian
terhadap aspek sosial dan keagamaan lebih diutamakan daripada aspek materi.
Menurut Wolf (1983:2), peasant merupakan orang desa yang bercocok tanam dan
berternak di daerah pedesaan. Usaha tani tersebut tidak dilakukannya sebagai
petani farmer atau pengusaha pertanian (agricultural enterpreneur) karena tidak
dilakukan sebagai kegiatan bisnis untuk meraih keuntungan ekonomis, namun
dilakukan dalam kerangka pengelolaan rumah tangga.
30
Dalam melakukan produksi pertanian, peasant harus mengarahkan
kegiatannya untuk melayani keluarga dan masyarakat. Hal ini sebagaimana
dikemukakan oleh Diaz (1967:50), yaitu bahwa peasant sebagai man economic
harus mengarahkan aktivitasnya dalam dua ruang, yakni ruang keluarga dan ruang
masyarakat. Perhatian peasant terhadap keluarga dan masyarakatnya dikemukakan
pula oleh Popkins (1979:28), yaitu bahwa pihak-pihak yang menjadi perhatian
utama peasant adalah diri sendiri, keluarga, tetangga, dan komunitas desanya. Di
dalam ruang keluarga maupun ruang masyarakat, peasant memberi dukungan
dengan produksi usaha tani yang dilakukan dalam kondisi kesederhanaannya
dengan teknologi non-industri dan bertumpu pada rumah tangga (household
based), serta produksi pertanian berorientasi subsistensi (Elson, 1997:xix).
Menurut Scott (1981:7), usaha subsistensi adalah usaha tani yang mengutamakan
keamanan (safety first). Dalam kehidupan tertib sosial masyarakat, peasant perlu
selalu menjaga relasi antarrumah tangga dan memelihara keseimbangan antara
kepentingan keluarga dan masyarakat yang dapat mengikat peasant dengan
masyarakat yang lebih luas. Menurut Wolf (1983:170), dalam kerangka ini
upacara atau ritual memiliki suatu fungsi melegetimasi unit sosial dan relasi di
antara sesama warga desa. Selain itu dari sudut komunikasi sosial, hal ini dapat
mengukuhkan eksistensi peasant dalam komunitasnya. Sebagai produsen
pertanian berskala kecil, tindakan dan pilihan petani selalu dikaitkan dengan
sumber daya alam, seperti tanah, air, iklim, dan matahari. Dengan demikian
peasant memiliki hubungan yang kuat dengan sistem ekologis (Weizt (1971:19).
Kuatnya pertalian peasant dengan kondisi ekologis menciptakan pula prosedur
dalam melakukan usaha tani. Keadaan ini menyebabkan petani akan sangat
31
berhati-hati dalam menerima introduksi teknologi baru. Dalam pandangan
peasant, perubahan teknologi sekecil apapun akan membawa pada konsekuensi
yang tidak terantisipasi yang dapat mengancam sistem produksi pertanian (Weitz,
1971:9).
Dalam menerima teknologi baru yang berimplikasi adanya prosedur yang
berbeda dengan kebiasaan bertani, petani menggunakan pola pikir safety first
demi keamanan subsistensinya. Analisis Scott (1981:3) menemukan bahwa etika
subsistensi di kalangan petani Asia Tenggara merupakan akibat dari kehidupan
petani yang dekat dengan garis batas yang merupakan garis antara keamanan dan
risiko Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa dalam perspektif moral ekonomi
petani, peasant merupakan golongan petani yang selalu menentang risiko.
Soekartawi (2003:173) mengemukakan bahwa agribisnis terdiri dari petani
yang selalu melakukan upaya memaksimalkan pendapatan dengan penguasaan
sumber daya yang terbatas. Adapun cirinya, pertama, cepat mengadopsi inovasi
sehingga digolongkan sebagai pengadopsi awal (early adopters). Kedua, memiliki
derajat kosmopolitan yang tinggi. Ketiga, memiliki keberanian menanggung risiko
dalam berusaha tani. Keempat, memiliki sikap mau dan kemampuan mencoba
teknologi baru yang ditunjang oleh sumber daya yang memadai. Slamet (2003:16)
mengemukakan bahwa untuk peningkatan produksi dalam pembangunan
pertanian diperlukan teknologi maju. Oleh karena itu petani perlu mengadopsi
teknologi maju. Dalam perspektif penyuluhan pembangunan, petani maju adalah
petani yang memiliki kemampuan untuk memerankan diri sebagai warga negara
yang baik sesuai dengan profesinya, dan sanggup berswadaya untuk
meningkatkan kesejahteraannya sendiri dan masyarakatnya (Slamet, 2003:18).
32
Pambudy (2003:235) mengemukakan bahwa seorang usahawan agribisnis
merupakan orang yang mampu untuk menyelesaikan proses dari menghasilkan ide
kreatif, inovasi, hingga menghasilkan produk barang atau jasa untuk dapat
dipasarkan dengan keuntungan yang memadai. Selain sebagai petani komersial
berbudaya industri, farmer juga dapat digolongkan sebagai petani modern.
Menurut Suriasumantri (2000:384), masyarakat modern yang urban memiliki
indikator sebagai berikut, pertama, bersifat analitik. Di samping itu, sebagian
besar aspek kehidupannya dilandaskan pada asas efisiensi secara teknis maupun
ekonomis. Indikator ini menempatkan nilai teori dan nilai ekonomi pada posisi
penting. Nilai teori terkait dengan aspek penalaran, ilmu, dan teknologi,
sedangkan nilai ekonomi berpusat pada penggunaan sumber dan benda ekonomi
secara efektif dan efisien berlandaskan perhitungan yang bertanggung jawab.
Sementara itu pengambilan keputusan berlandas pada argumentasi kuat. Kekuatan
berpikir bersifat dominan yang mengabaikan penarikan kesimpulan dari intuisi,
perasaan, dan tradisi. Kedua, bersifat individual. Nilai sosial dan kekuasaan dalam
kerangka ini harus berorientasi pada kepercayaan diri sendiri serta keberanian
untuk mengambil keputusan sendiri. Hubungan antarmanusia bersifat individual,
sementara untuk mempertahankan hidup seseorang harus mampu bersaing secara
produktif. Perbedaan budaya lainnya dari peasant dan farmer lainnya dapat
dikaitkan dengan dikotomi budaya yang dapat dijelaskan dengan konsep orientasi
nilai dari Kluckhohn dan Strodtbeck, individualisme-kolektivisme, variabilitas
budaya Hofstede, Pola-pola Parsons, dan keketatan Struktral.
33
A. Orientasi Nilai dari Kluckhohn-Strodtbeck
Kluckhohn-Strodtbeck memunculkan dimensi orientasi nilai. Dimensi ini
terdiri dari orientasi sifat manusia, orientasi sifat orang, oientasi waktu, aktivitas,
dan orientasi relasional (Gudykunst dan Kim, 1997:78). Dimensi pertama adalah
orientasi sifat manusia yang terkait dengan sifat bawaan. Dalam dimensi ini,
manusia dipandang baik atau jahat atau campuran antara baik dan jahat yang
merupakan pembawaan sejak lahir. Dimensi kedua, orientasi relasi manusia dan
alam. Ada tiga jenis relasi, yaitu takluk, menyelaraskan, dan mengendalikan.
Dimensi ketiga, orientasi waktu. Dalam dimensi ini, kehidupan manusia dapat
berfokus pada masa lalu, masa kini, atau, masa depan. Orientasi yang kuat
terhadap masa lalu cenderung menonjol pada kelompok budaya yang
menempatkan tradisi dalam posisi yang utama, seperti pemujaan pada leluhur atau
yang memberi tekanan lebih pada kohesivitas keluarga. Dimensi keempat,
orientasi aktivitas. Menurut Kluckhon-Strodtbeck, orientasi aktivitas dapat
dipandang sebagai doing, being, dan being-in-becoming. Orientasi doing berfokus
pada jenis aktivitas yang memiliki keluaran eksternal yang dapat diukur. Oleh
karena itu aktivitas ini harus nyata. Dalam kerangka ini terdapat pula orientasi
pada capaian hasil. Dimensi kelima, orientasi relasional. Orientasi relasional
terkait dengan dimensi individualisme-kolektivisme. Keterkaitan itu adalah karena
cara orang berinteraksi memiliki fokus yang berbeda, yaitu ke arah individualisme
atau kolektivisme.
Kluckholn dan Strodtbeck (1961) membandingkan budaya berdasarkan
atas beberapa dimensi sebagai berikut :
34
1. Nature of People (Karakter dasar manusia)
Budaya yang berorientasi pada sifat manusia membagi karakter manusia
menjadi: baik, buruk, dan campuran antara baik dan buruk. Masyarakat Barat,
umumnya, memandang manusia memiliki karakter yang baik, sedangkan
masyarakat Timur (misalnya Cina) memandang manusia memiliki sifat baik
atau buruk. Orientasi seperti ini memiliki konsekuensi yang sangat berarti
dalam bersikap kepada orang lain, baik dalam aspek kepercayaan atau interaksi
dengan orang lain.
2. Relationship to The Environment (Hubungan dengan alam lingkungan)
Pada budaya yang berorientasi pada alam, berkaitan dengan cara manusia
memperlakukan lingkungannya. Manusia dapat menguasai atau mengungguli
lingkungan, hidup selaras dengan lingkungan, atau menaklukkan (subjugate)
lingkungannya. Masyarakat Barat berpendirian bahwa mereka dapat
mengendalikan lingkungan dan semua kekuatan alam (misalnya badai, banjir).
Masyarakat Timur berpendirian bahwa manusia harus hidup selaras dengan
lingkungannya dan bahkan memujanya. Orientasi terhadap lingkungan
mempengaruhi sikap manusia terhadap agama, estetika, kepemilikan benda,
kualitas hidup, dan hubungan terhadap manusia lainnya.
3. Activity Orientation (Orientasi Aktivitas)
Orientasi terhadap aktivitas manusia berkaitan dengan sikap manusia
terhadap suatu aktivitas atau kegiatan. Ada masyarakat yang berorientasi
“melakukan” (doing), misalnya masyarakat Amerika dan Jerman, mereka lebih
menekankan kepada aktivitas atau kegiatan, penyelesaian tugas, berkompetisi,
dan pencapaian tujuan. Selain itu ada masyarakat yang berorientasi “menjadi”
35
(being). Orang mmelakukan berbagai aktivitas secara spontan, memperturutkan
kesenangan, dan menunjukkan spontanitasnya sebagai ekspresi
kepribadiannya. Kelompok lainnya adalah kelompok masyarakat yang
berorientasi kepada “the being –in-becoming” (yang menjadi). Masyarakat ini
lebih tertarik kepada kehidupan spiritual daripada kehidupan material.
4. Time Orientation (Orientasi waktu)
Orientasi terhadap waktu berkaitan dengan dengan sikap manusia terhadap
waktu. Orang dapat memusatkan diri ada masa lampau, saat ini, atau masa
yang akan datang. Masyarakat Barat lebih berorientasi pada masa yang akan
datang (future). Mereka menganggap bahwa waktu sebagai sesuatu yang harus
dihargai, oleh karena itu harus dipergunakan secara efektif. Sebaliknya,
masyarakat Timur, lebih berorientasi kepada masa lalu (past) dan tradisi.
Mereka memuja leluhur dan memiliki tradisi keluarga yang kuat (misalnya
masyarakat Jepang dan Cina). Masyarakat yang berorientasi pada waktu
sekarang (present), percaya bahwa waktu sangat berarti. Orang Filipina,
Meksiko, dan Amerika Latin pada umumnya berorientasi pada waktu saat ini.
5. Focus of Responsibility (Fokus tanggung jawab)
Orientasi terhadap tanggung jawab pada orang lain merupakan aspek yang
sangat penting berkaitan dengan hubungan antar manusia dan paling
membedakan anatara budaya Barat dengan budaya Timur. Kluckhohn &
Strodtbeck, 1961, dalam Reisinger (2009: 130) menyebutkan tiga jenis
orientasi terhadap orang lain: (1) individualistik (tujuan-tujuan individu
mengatasi tujuan-tujuan kelompok); (2) collateral (individu merupakan bagian
dari suatu kelompok sosial yang diakibatkan oleh hubungan yang diperluas
36
secara menyamping (laterally); dan (3) linear (mengutamakan keberlanjutan
kelompok melalui penggantian waktu).
6. Conception of Space (Konsepsi tentang ruang)
Konsepsi keruangan menurut kerangka Kluchkohn dan Strodtbeck
berhubungan dengan kepemilikan ruang. Beberapa budaya menganggap bahwa
tempat atau ruang harus tetap dijaga sebagai milik pribadi, sementara
kebudayaan lain menganggap bahwa sebuah ruang/tempat sangat terbuka
bahkan sangat dianjurkan untuk mengembangkan bisnis di publik. Beberapa
kelompok masyarakat menggabungkan antara publik dan privat.
Table 2.1
Cultural Orientations and Dimensions
No. Dimensi Indikator
I Nature of humans (karakter dasar manusia)
Good/Evil: The basic nature of people is essentially good (lower score) or evil (higher score).
Changeable/Unchangeable: The basic nature of humans is changeable (higher score) from good to
evil or vice versa, or not changeable (lower score).
II Relationships among people / focus responsibility (Hubungan dengan orang lain / fokus tangungjawab)
Individual: Our primary responsibility is to and for ourselves as individuals, and next for our immediate families.
Collective: Our primary responsibility is to and for a larger extended group of people, such as an extended family or society.
Hierarchical: Power and responsibility are naturally unequally distributed throughout society; those higher in the hierarchy have power over and responsibility for those lower.
III Relation to broad environment (hubungan dengan lingkungan)
Mastery: We should control, direct and change the environment around us.
Subjugation: We should not try to change the basic direction of the broader environment around us, and we should allow ourselves to be influenced by a larger natural or supernatural element.
Harmony: We should strive to maintain a balance
37
among the elements of the environment, including ourselves.
IV Activity (aktivitas) Doing: People should continually engage in activity to accomplish tangible tasks.
Thinking: People should consider all aspects of a situation carefully and rationally before taking action.
Being: People should be spontaneous, and do everything in its own time.
V Time (waktu) Past: Our decision criteria should be guided mostly by tradition.
Present: Our decision criteria should be guided mostly by immediate needs and circumstances.
Future: Our decision criteria should be guided by predicted long term future needs and circumstances.
VI Space (ruang)
Public: The space around someone belongs to everyone and may be used by everyone.
Private: The space around someone belongs to that person and cannot be used by anyone else without permission.
Diadopsi dari Kluckholn and Strodbeck (1961) dalam See Lane et al. (2000)
B. Variabilitas Budaya Hofstede
Menurut Hofstede (1994:109), ketidakpastian dirasakan dan dipelajari oleh
seorang anggota budaya dari warisan budaya yang dipindahkan serta digerakkan
melalui institusi dasar, seperti keluarga dan sekolah. Perasaan itu direfleksikan ke
dalam nilai yang dipegang secara kolektif oleh anggota masyarakat, serta
kemudian menuntun pola perilaku kolektif suatu masyarakat yang tidak mudah
dipahami oleh masyarakat lainnya.
Para anggota budaya yang berderajat tinggi dalam menghindari
ketidakpastian memiliki toleransi yang rendah pada ketidakpastian dan sesuatu
yang sifatnya ambigu. Para anggota dari kelompok budaya ini juga memiliki
kebutuhan yang besar akan adanya peraturan formal dan kebenaran mutlak. Selain
itu juga kurang memberi toleransi pada ide atau perilaku yang menyimpang dari
38
peraturan formal. Sementara itu, orang dari kelompok budaya yang memiliki
derajat rendah dalam menghindari ketidakpastian akan memiliki karakteristik
yang berlawanan dengan orang-orang yang memiliki derajat tinggi dalam
menghindari ketidakpastian.
Dimensi maskulinitas-feminitas (Hofstede dalam Ting-Toomey, 1999:72)
terkait dengan masyarakat yang dengan jelas membedakan karakteristik peran
jender. Karakteristik seperti laki-laki lebih asertif, keras, dan memiliki fokus pada
keberhasilan material, sementara perempuan yang cenderung rendah hati, lembut,
dan berfokus pada kualitas hidup. Hofstede (1994:81) dalam konteks organisasi
mengemukakan bahwa pada kutub maskulin, terdapat kesempatan untuk meraih
pendapatan yang tinggi, pengakuan layak yang berkaitan dengan prestasi,
kemajuan menuju tataran pekerjaan yang lebih tinggi, serta memiliki tantangan
dalam pekerjaan. Sementara itu pada kutub feminin terdapat relasi kerja yang
baik, kerjasama yang baik, dan keamanan dalam melakukan pekerjaan. Suatu hal
lagi yang menjadi pembeda antara budaya maskulin dan feminin adalah pada cara
atau proses peranan jender didistribusikan dalam suatu kelompok budaya. Para
anggota budaya maskulin akan berorientasi pada ambisi, benda atau materi,
kekuasaan, dan ketegasan, sementara para anggota budaya feminin akan memberi
nilai yang tinggi pada kualitas hidup, pelayanan, perhatian pada orang lain di
dalam kelompok, dan pemeliharaan hubungan.
C. Pola-pola Parsons
Dimensi pola-pola Parsons berbentuk dikotomi situasi. Satu sisi dapat
dipilih oleh seorang pelaku komunikasi dengan mempertimbangkan konteks
situasinya. Pola ini terdiri dari afektivitas-netralitas afektif, universalisme-
39
partikularisme, ketersebaran-keterkhususan, askripsi-prestasi, orientasi
instrumental-ekspresif (Gudykunst dan Kim, 1997:78). Pertama, afektivitas-
netralitas afektif. Orentasi pola ini berkenaan dengan sifat kepuasan yang dicari
oleh manusia. Sisi afektivitas menjadi posisi dari orang yang mencari kepuasan
segera dari situasi yang ada. Kedua, universalisme-partikularisme. Orientasi
universalistik berfokus pada kategorisasi orang atau obyek dalam konteks
referensi universal, sedangkan orientasi partikularistik berfokus pada kategorisasi
orang atau obyek secara spesifik. Ketiga, ketersebaran-keterkhususan. Orientasi
ini berfokus pada cara orang memberi respon pada orang lain. Dengan orientasi
ketersebaran, respon holistik akan diberikan seseorang kepada orang lain,
sedangkan orientasi keterkhususan ditampakkan seseorang dengan memberi
respon terhadap orang lain dalam cara yang khusus Keempat, askripsi-prestasi.
Orientasi askripsi dari seseorang akan tampak ketika orang tersebut memandang
orang lain. Dengan orientasi askriptif, pandangan seseorang akan bertolak pada
prediksi sosiokultural, yakni dalam kerangka keanggotaan orang lain di dalam
kelompoknya, seperti jender, umur, ras, etnik, kasta, dan sebagainya. Sementara
orang dengan orientasi prestasi akan mendasarkan prediksi dalam kerangka
prestasi yang dapat diraih orang lain. Kelima, orientasi instrumental-ekspresif.
Orientasi instrumental ditampakkan oleh orang dalam interaksinya dengan orang
lain jika interaksi itu merupakan sarana untuk mencapai tujuan lainnya, sedangkan
orientasi ekspresif akan tampak pada orang yang interaksinya dengan orang lain
merupakan tujuannya.
Keketatan struktural merupakan dimensi yang berfokus pada norma,
aturan, dan batasan yang berlaku pada anggota suatu komunitas. Budaya yang
40
longgar hanya menerapkan sedikit peraturan dan batasan atas perilaku, sementara
di dalam budaya yang ketat aturan dan batasan perilaku, norma dan aturan budaya
cenderung jelas dan harus ditaati. Dalam budaya ketat, jika ada anggota
komunitas yang melanggar norma dan aturan budaya dikenakan sanksi.
Sebaliknya dalam komunitas budaya longgar, para anggota yang melanggarnya
tidak akan dikenai sanksi sekeras pada budaya ketat (Gudykunst dan Kim,
1997:81).
2.1.5 Kebudayaan Indonesia
Beragamnya budaya nasional di Indonesia secara otomatis mempengaruhi
gaya kepemimpinan lewat para pengikut. Pemimpin tidak dapat memilih gaya
kepemimpinan mereka, karena dikendalikan oleh kondisi budaya yang ternyata
diharapkan oleh pengikut mereka (Bowo, 2008). Untuk tipe kepemimpinan di
Indonesia, budaya nasional sangat kental diterapkan dalam gaya kepemimpinan
seseorang. Walaupun gaya kepemimpinan dari setiap suku atau budaya berbeda-
beda, namun demikian secara umum telah ada tipologi gaya kepemimpinan
nasional yang menunjukan adat ketimuran bangsa Indonesia (Bowo, 2008).
Menurut Munandar (2001) di Indonesia kita kenal sebelas ciri pribadi yang
diharapkan oleh seorang pemimpin, antara lain:
a. Takwa, menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha
Esa dan taat kepada segala perintah-Nya.
b. Ing Ngarsa Sung Tuladha, sebagai pemula, orang yang berada di depan,
selalu memberi suri teladan kepada yang dipimpinnya.
41
c. Ing Madya Mangun Karsa, ditengah-tengah para anak buahnya ikut terjun
langsung bekerja sama bahu membahu, memberi dorongan, semangat.
d. Tut Wuri Handayani, dari belakang selalu memberi dorongan dam arahan
kepada apa yang diinginkan anak buahnya.
e. Waspada Purba Wisesa, selalu berhati-hati dalam segala kondisi, meneliti
dan membuat perkiraan keadaan secara terus-menerus.
f. Ambeg Para Maarta, pandai menentukan mana yang menurut ruang, waktu
dan keadaan patut didahulukan.
g. Prasaja, bersifat dan bersikap sederhana serta rendah hati dan correct.
h. Satya, loyalitas timbal-balik dan bersikap hemat, tidak ceroboh serta
memelihara kondisi materiil dengan kecermatan.
i. Gemi nastiti, hemat dan cermat, sadar dan mampu membatasi penggunaan
dan pengeluaran hanya untuk yang benar-benar diperlukan.
j. Belaka, bersifat dan bersikap terbuka, jujur dan siap menerima segala kritik
yang membangun, selalu mawas diri dan selalu siap
mempertanggungjawabkan perbuatannya.
k. Legawa, rela dan ikhlas untuk pada waktunya mengundurkan diri dari fungsi
kepemimpinannya dan diganti dengan suatu generasi baru yang telah
mewarisi kesepuluh ciri ini.
Ciri-ciri pribadi tersebut lebih berfungsi sebagai prinsip-prinsip yang harus
dijalankan, sehingga mempunyai makna sebagai pedoman yang sifatnya normatif.
De Bono, 1986 (dalam Munandar, 2001) berdasarkan wawancaranya
dengan lima puluh pria dan wanita yang sangat berhasil dalam bidangnya masing-
masing berkesimpulan bahwa ada empat macam faktor (dua ciri pribadi dan dua
42
lainnya merupakan faktor di luar dirinya) yang menentukan keberhasilan
seseorang atau sekelompok orang. Kedua ciri pribadi itu adalah:
a. A little madness, orang yang tahu dengan pasti dan jelas apa yang ia inginkan
dan memiliki dorongan yang sangat kuat untuk mencapai tujuannya.
b. Very talented, orang yang mempunyai bakat yang sangat menonjol di bidang
tertentu.
c. Rapid growth field. Orang yang bekerja dalam bidang yang berkembang
sangat cepat mempunyai peluang lebih banyak untuk berhasil, daripada orang
yang bekerja di bidang yang tidak dapat berkembang dengan cepat. Bidang
teknologi, khususnya komputer merupakan bidang yang cepat berkembang
dengan cepat. Keadaan ini memungkinkan bakat untuk berkembang.
d. Luck. Ada orang yang kebetulan berada di tempat pada saat yang tepat untuk
melakukan usahanya. Ada orang lain yang selalu kesulitan dalam memulai
usahanya.
Selain itu, ciri kebudayaan pribadi bangsa Indonesia lainnya yang sangat
banyak berpengaruh dalam kehidupan berorganisasi adalah bermusyawarah
menuju mufakat, dan memutuskan segala sesuatu atas dasar konsensus diantara
seluruh kelompok organik, sekurang-kurangnya diantara kelompok seangkatan
pengalaman (peer group).
2.1.6 Kebudayaan Korea
Berdasarkan sudut pandang antropologis dan sosiologis, karakteristik-
karakteristik kebudayaan tradisional Korea dengan fokus pada sistem keluarga
43
dan pengaruh yang ditimbulkan terhadap gaya manajemen korea atau budaya
organisasi, adalah sebagai berikut (Cho, 1995).
1. Keselarasan dan Stabilitas
Konfusianisme mengatur norma-norma perilaku bagi orang Korea yang telah
berlangsung selama 500 tahun Dinasti Chosun. Sampai saat ini pengaruh ajaran
konfusianisme masih besar peranannya dalam kehidupan keluarga dan sosial.
Menurut semangat dasar konfusianisme tradisional, loyalitas dan kewajiban antara
raja dan rakyatnya merupakan suatu keharusan, hubungan erat antara kedua orang
tua dan anakanak adalah penting dan perlu, peran-peran yang berbeda ada di
antara kaum tua dan kaum muda; dan harus ada keyakinan antara teman. Artinya
etika mengenai hubungan vertikal dan horisontal harus diamati agar bisa
menetapkan stabilitas dalam keluarga dan masyarakat melalui keselarasan (Hahn,
1988). Dengan demikian, konfusianisme memiliki pengaruh yang besar terhadap
ideologi manajemen, perilaku organisasi, sistem manajemen dan hubungan
manusia. Perusahaan Korea secara khas menekankan keselarasan, kesatuan dan
kerjasama, kreativitas dan pengembangan. Banyak sekali perusahaan mengaku
bahwa stabilitas sebagai tujuan utama karena latar belakang kultur (budaya)
manajemen, dimana keselarasan di kalangan para anggota dan pengembangan
keseluruhan organisasi yang stabil lebih disukai daripada moral progresif dan
pertumbuhan yang cepat. Sehubungan dengan latar belakang kebudayaan
tradisional tersebut maka orang korea lebih menekankan manajemen personalia
termasuk hubungan-hubungan manajemen tenaga kerja.
44
2. Suksesi yang Tidak Setara
Warisan kekayaan keluarga dalam sistem keluarga Korea berbentuk warisan
yang tidak setara di mana anak laki-laki tertua diberi perlakuan istimewa. Dalam
kehidupan keluarga Korea, ada sistem yang disebut keluarga utama yang akan
digantikan oleh anak-laki-laki tertua. Dari anak laki-laki kedua dan seterusnya ke
bawah, ada sistem yang disebut cabang dari keluarga tersebut. Pada waktu
tertentu, meskipun ada kekayaan yang cukup untuk didistribusikan secara merata
di kalangan anak laki-laki, lazimnya saham terbesar diberikan kepada anak laki-
laki tertua. Pembagian warisan yang tidak setara ini memiliki makna yang penting
ketika diterapkan pada suksesi suatu perusahaan. Namun demikian, dalam banyak
perusahaan di Korea, tidak semua otoritas pendiri dipindahkan kepada
penerusnya. Meskipun si penerus tidak mewarisi posisi tersebut, kekuasaan
memerintah yang mutlak dan pengaruh yang dulu dimiliki si pendiri tidak secara
langsung diterima oleh para anggota organisasi dan kelompok-kelompok
kepentingan lainnya. Jika suksesi tidak setara diterapkan dalam perusahaan maka
sebaiknya para penerima warisan yang akan meneruskan kepemimpinan diberikan
pembelajaran terlebih dahulu. Artinya pembelajaran yang dimaksud adalah ikut
dilibatkan seseorang calon pewaris (si penerus) dalam melakukan pengelolaan
usaha, membuat keputusan usaha, dengan tujuan agar calon pewaris (si penerus)
tidak awam sama sekali pada usaha orang tuanya dan bisa melanjutkan usahanya.
3. Eksklusivisme dan Sentralisasi Kekuasaan
Dalam kehidupan sosial tradisional Korea, pertalian darah dan status sosial
mengandung latar belakang sikap orang Korea yang menimbulkan suatu cara
berpikir yang eksklusif dan tertutup. Hal ini juga berlaku pada masyarakat Korea
45
secara umum di dalam kerangka kehidupan yang eksklusif dan tertutup yang
dipelihara tersebut, kekuasaan yang diperlukan untuk menjaga urutan keluarga
dikonsentrasikan pada kepala keluarga dan anggota keluarga yang tertua yang
membentuk suatu struktur otoritas kekuasaan yang tersentralisir. Dalam
melakukan ritus-ritus pengorbanan bagi pemujaan leluhur yang merupakan
perluasan dari ketaatan anak laki-laki atau perempuan, keluarga langsung
memiliki prioritas tersebut. Para kerabat dekat dan jauh, kaum manula dan kaum
muda semua dibedakan, begitu juga yang berhubungan darah dan yang tidak.
Bahkan di antara hubungan pribadi, orang-orang yang intim dan orang-orang yang
tidak intim juga dibedakan sehingga merangsang timbulnya fraksionalisme
(faham berdasarkan golongan). Prinsip tradisional sikap eksklusif dan sentralisasi
kekuasaan juga menimbulkan dampak yang besar terhadap struktur kekuasaan
dalam berbagai perusahaan bisnis Korea. Prinsip ini lebih jelas dipraktikkan oleh
individu atau kelompok yang memiliki hak kepemilikan atas perusahaan, ketika
mengamankan dan mempertahankan hak-hak pengelolaan.
4. Prinsip Senioritas
Prinsip ini digunakan dalam organisasi manajemen Korea sebagai standar
yang digunakan untuk meningkatkan atau menaikkan gaji yang didasarkan pada
prinsip personal. Prinsip personal adalah suatu prinsip yang dapat digunakan
secara universal dan berlaku pada semua orang ketika mengevaluasi seseorang
dalam kehidupan sosial Korea. Pertimbangan khusus diberikan pada personal
yang telah berdinas lama dan mengundurkan diri untuk kesejahteraan hidup
mereka. Prinsip senioritas dapat penulis katakan sebagai penghargaan yang
diberikan oleh perusahaan pada karyawan senior, karena mereka sudah ikut
46
berjuang membesarkan perusahaan, dan pengorbanannya selama ini diakui oleh
perusahaan dengan cara memberikan tingkat kesejahteraan lebih tinggi
dibandingkan karyawan junior. Peran anggota-anggota keluarga juga ditentukan
menurut derajat. Banyak kelas dan urutan derajat sangat ketat dalam keluarga
dengan kepala keluarga sebagai pusat. Masing-masing individu melakukan
kewajibannya sendiri menurut urutannya dalam derajat: ayah, suami, istri dan
anak (Shin, 1984).
5. Otoritas Patriarkal dan Keselarasan
Dalam kehidupan keluarga tradisional Korea, ayah memiliki hak sebagai
kepala keluarga dan hak sebagai ayah, sehingga ia menggunakan otoritas mutlak
dan sepihak (sistem patriarkal) untuk mengatur orang-orang di bawahnya guna
kesejahteraan keluarga. Namun demikian kepala keluarga tidak selalu
menggunakan otoritas sepihak, ia juga menekankan keselarasan, memperlakukan
keluarga dengan hangat, mengendalikan dan mendorong aktivitas anggota
keluarganya (dikendalikan juga oleh orang yang lebih tua) untuk memperoleh
kepatuhan mereka. Metode kontrol berdasarkan otoritas dan keselarasan dalam
kehidupan keluarga tradisional ini mempengaruhi kepemimpinan manajemen
dalam dua cara, yaitu: (1) para anggota perusahaan sadar bahwa otoritas
tradisional para senior dalam derajat ditetapkan secara luas; (2) dalam cara yang
sama, keselarasan sangat ditekankan dalam organisasi.
6. Kepatuhan dan Ketundukan
Norma-norma perilaku masyarakat Korea didasarkan pada konsep kepatuhan
anak-anak pada orang tua (terlihat jelas pada hubungan ayah dengan anak laki-
lakinya). Dalam kehidupan sehari-hari orang harus berbicara dengan penuh
47
hormat, bersikap beradap terhadap orang lain di luar keluarga yang lebih tua atau
memiliki posisi lebih tinggi. Seseorang harus mengidentifikasi dirinya dalam
kelompok sosial tersebut (sense of belonging), dan menunjukkan rasa hormat
pada orang-orang di atasnya. Cara berpikir tradisional ini mempengaruhi
hubungan vertikal antara para majikan dan karyawan. Anggota perusahaan Korea
menganggap hubungan vertikal lebih penting daripada hubungan horisontal.
Penekanan pada hubungan vertikal menimbulkan komunikasi ke bawah secara
sepihak dan merupakan alasan bagi timbulnya konsentrasi pengambilan keputusan
pada tingkattingkat atas organisasi tersebut.
2.2. Penelitian Terdahulu
Ada beberapa penelitian perihal kepemimpinan yang sudah dilakukan.
Akan tetapi, penelitian yang langsung meneliti model kepemimpinan seorang
pemimpin di suatu perusahaan, terutama perusahaan surat kabar, barulah sedikit.
Namun, untuk menambah khazanah keilmuan serta yang menjadi inspirasi saya
dalam melakukan penelitian tentang model kepemimpinan seorang pemimpin di
suatu perusahaan ini, maka saya akan menyebutkan beberapa penelitian bertema
kepemimpinan yang sudah pernah dilakukan, antara lain:
1. Vesa Suutari, Kusdi Raharjo, dan Timo Riikkila (2002)
Judul : The Chalenge of Cross-cultural Leadership Interaction: Finnish
expatriates in Indonesia
Meneliti interaksi kepemimpinan lintas budaya para manajer ekspatriat dari
Finlandia terhadap karyawan yang merupakan penduduk lokal dalam
perusahaan multi nasional dari Finlandia yang ada di Indonesia.
48
2. Lieh-Ching Chang (2002)
Judul : Cross-cultural Differences in Internasional Management Using
Kluckhohn-Strodtbeck Framework
Meneliti gaya kepemimpinan manajer internasional yang melakukan
pekerjaan di luar negerinya dan pentingnya bagi para manajer
internasional untuk mengetahui mengenai perbedaan budaya nasional di
masing-masing negara.
3. Yoo Keun Shin (1999)
Judul : The Traits and Leadership Styles of CEO’s in Korean Companies
Meneliti gaya kepemimpinan para CEO di beberapa perusahaan Korea dan
mengidenttifikasi bagaimana pengikutnya menerima gaya kepemimpinan
tersebut..
4. Rachel K (2004)
Judul : Culture, Intercultural Communication Competence, and Sales
Negotiation: a Qualitative Research Approach
Meneiliti perbedaan kebudayaan dalam perusahaan, kompetensi
komunikasi lintas budaya yang efektif dalam rangka meningkatkan
kualitas negosiasi antar karyawan baik di dalam perusahaan maupun ke
luar perusahaan untuk negosiasi penjualan.
5. Aya Fukushige dan David P. Spicer (2007)
Judul : Leadership Preference in Japan : An Exploratory Study
Meneliti mengenai preferensi kepemimpinan di Jepang dengan
menggunakan dimensi penilaian budaya Bass dan Avolio serta
mengidentifikasi para pengikut atau follower Jepang mengenai gaya
49
kepemimpinan kontemporer Jepang serta mengidentifikasi faktor-faktor
lain di luar dimensi Bass dan Avolio.
2.3. Kerangka Pikir
Adapun skema kerangka pikir teoretis dalam pandangan peneliti adalah
sebagai berikut:
Perusahaan internasional Kukdong Corporation memiliki perluasan usaha
yang berada di Semarang Indonesia berupa perusahaan multi nasional PT.
Semarang Garment. Perusahaan tersebut menempatkan pimpinan serta jajaran
manajer ekspatriat yang berasal dari negaranya yaitu Korea Selatan. Para
Sumber : Diadopsi dari Dimensi Budaya Kluckholn&Strodtbeck dan Pola-pola Parson, 2013
Home
Country
Korea
Host
Country
Indonesia
Budaya
nasional
Korea
Budaya
nasional
Indonesia
kepemimpin
an
followers
/pengikut
Proses
penerimaan
budaya
Bentuk
kepemimpin
an gaya
Korea di
Indonesia
Dimensi Kluckholn & Strodtbeck
Nature of humans
Focus responsibility
Relation to broad environment
Activity
Time
space
Pola-pola Parson
afektivitas-netralitas afektif
universalisme-partikularisme
ketersebaran-keterkhususan
askripsi-prestasi
orientasi instrumental-ekspresif
50
pemimpin ini membawahi sejumlah karyawan yang merupakan penduduk lokal.
Dengan demikian, perbedaan budaya yang ada merupakan suatu tantangan bagi
perusahaan, khususnya jajaran manajer yang sebaiknya memiliki kemampuan
kepemimpinan lintas budaya secara efektif agar mampu mengembangkan
perusahaan dan berinteraksi dengan baik bersama bawahannya meskipun dengan
latar belakang budaya yang berbeda. Kepemimpinan gaya Korea yang diterapkan
oleh manajer ekspatriat berkebudayaan Korea di perusahaan PT. Semarang
Garment dan bagaimana para pengikut lokal berkebudayaan Indonesia menerima
kepemimpinan tersebut merupakan fokus dari studi ini. Untuk mengidentifikasi
hal tersebut, penelitian ini akan dibatasi beberapa variabel budaya dari kerangka
Kluckholn& Strodtbeck serta pola-pola Parson.
51
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2007), pendekatan penelitian kualitatif
merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa
yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi,
tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk
kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Salah satu tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk meneliti suatu
objek secara mendalam. Hal ini sesuai dengan penelitian ini, dimana akan melihat
gaya kepemimpinan Korea di Indonesia secara mendalam melalui beberapa
variabel yang membatasi penelitian. Pendekatan yang digunakan terkait dengan
penelitian kualitatif ini adalah pendekatan studi kasus (case study) dimana
pendekatan yang demikian memusatkan diri secara intensif pada satu obyek
tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Dalam studi kasus, dapat
diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi
ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003). Studi kasus
mengumpulkan beberapa sumber dan hasil penelitian yang hanya berlaku pada
kasus yang diselidiki. Lebih lanjut Arikunto (1986) mengemukakan bahwa
metode studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah
penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu
52
individu, lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subyek byang sempit.
Penelitian studi kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang
latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang
berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat
apa adanya. Subyek yang diteliti relatif terbatas tetapi menggunakan variabel
dengan dimensi tertentu. Pendekatan studi kasus yang digunakan oleh peneliti
akan membantu dalam proses penyelesaian penelitian kualitatif yang melihat dan
mendalami sebuah studi lintas budaya, khususnya kepemimpinan gaya Korea di
Indonesia pada satu perusahaan.
3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
3.2.1. Variabel Penelitian
Variabel penelitian pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang
berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga
diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya
(Sugiyono, 2008).
Penelitian ini akan menggunakan variabel penilaian budaya, khususnya
budaya nasional. Variabel tersebut menjadi pusat perhatian peneliti. Dengan
mengenali lebih jauh variabel tersebut, maka akan mudah melihat hakekat sebuah
masalah yang diteliti.
3.2.2. Definisi Operasional
Peneliti menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif
diakarenakan penelitian kualitatif bersifat fleksibel, luwes, dan terbuka
53
kemungkinan bagi suatu perubahan dan penyesuaian ketika proses penelitian
berjalan namun tetap dibatasi oleh variabel yang telah ditetapkan oleh peneliti.
Adapun penjelasan dari variabel yang peneliti gunakan, adalah:
Kerangka Budaya Kluckhohn dan Strodtbeck
Kluckholn dan Strodtbeck (1961) membandingkan budaya berdasarkan
atas beberapa dimensi sebagai berikut :
1. Nature of People
Budaya yang berorientasi pada sifat manusia membagi karakter manusia
menjadi: baik, buruk, dan campuran antara baik dan buruk. Masyarakat Barat,
umumnya, memandang manusia memiliki karakter yang baik, sedangkan
masyarakat Timur (misalnya Cina) memandang manusia memiliki sifat baik
atau buruk. Orientasi seperti ini memiliki konsekuensi yang sangat berarti
dalam bersikap kepada orang lain, baik dalam aspek kepercayaan atau interaksi
dengan orang lain.
2. Relationship to The Environment
Pada budaya yang berorientasi pada alam, berkaitan dengan cara manusia
memperlakukan lingkungannya. Manusia dapat menguasai atau mengungguli
lingkungan, hidup selaras dengan lingkungan, atau menaklukkan (subjugate)
lingkungannya. Masyarakat Barat berpendirian bahwa mereka dapat
mengendalikan lingkungan dan semua kekuatan alam (misalnya badai, banjir).
Masyarakat Timur berpendirian bahwa manusia harus hidup selaras dengan
lingkungannya dan bahkan memujanya. Orientasi terhadap lingkungan
mempengaruhi sikap manusia terhadap agama, estetika, kepemilikan benda,
kualitas hidup, dan hubungan terhadap manusia lainnya.
54
3. Activity Orientation
Orientasi terhadap aktivitas manusia berkaitan dengan sikap manusia
terhadap suatu aktivitas atau kegiatan. Ada masyarakat yang berorientasi
“melakukan” (doing) dimana mereka lebih menekankan kepada aktivitas atau
kegiatan, penyelesaian tugas, berkompetisi, dan pencapaian tujuan. Selain itu
ada masyarakat yang berorientasi “menjadi” (being). Orang mmelakukan
berbagai aktivitas secara spontan, memperturutkan kesenangan, dan
menunjukkan spontanitasnya sebagai ekspresi kepribadiannya. Kelompok
lainnya adalah kelompok masyarakat yang berorientasi kepada “thinking”
(yang memikirkan segala sesuatunya sebelum bertindak).
4. Time Orientation
Orientasi terhadap waktu berkaitan dengan dengan sikap manusia terhadap
waktu. Orang dapat memusatkan diri ada masa lampau, saat ini, atau masa
yang akan datang. Masyarakat Barat lebih berorientasi pada masa yang akan
datang (future). Mereka menganggap bahwa waktu sebagai sesuatu yang harus
dihargai, oleh karena itu harus dipergunakan secara efektif. Sebaliknya,
masyarakat Timur, lebih berorientasi kepada masa lalu (past) dan tradisi.
Mereka memuja leluhur dan memiliki tradisi keluarga yang kuat (misalnya
masyarakat Jepang dan Cina). Masyarakat yang berorientasi pada waktu
sekarang (present), percaya bahwa waktu sangat berarti.
5. Focus of Responsibility
Orientasi terhadap tanggung jawab pada orang lain merupakan aspek yang
sangat penting berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kluckhohn &
Strodtbeck, 1961, dalam Reisinger (2009: 130) menyebutkan tiga jenis
55
orientasi terhadap orang lain: (1) individualistik (tujuan-tujuan individu
mengatasi tujuan-tujuan kelompok); (2) collateral (individu merupakan bagian
dari suatu kelompok sosial yang diakibatkan oleh hubungan yang diperluas
secara menyamping (laterally); dan (3) linear (mengutamakan keberlanjutan
kelompok melalui penggantian waktu).
6. Conception of Space
Konsepsi keruangan menurut kerangka Kluchkohn dan Strodtbeck
berhubungan dengan kepemilikan ruang. Beberapa budaya menganggap bahwa
tempat atau ruang harus tetap dijaga sebagai milik pribadi, sementara
kebudayaan lain menganggap bahwa sebuah ruang/tempat sangat terbuka
bahkan sangat dianjurkan untuk mengembangkan bisnis di publik. Beberapa
kelompok masyarakat menggabungkan antara publik dan privat.
Pola-pola Parson
1. Afektivitas-netralitas afektif
Orentasi pola ini berkenaan dengan sifat kepuasan yang dicari oleh
manusia. Sisi afektivitas menjadi posisi dari orang yang mencari kepuasan
segera dari situasi yang ada.
2. Universalisme-partikularisme.
Orientasi universalistik berfokus pada kategorisasi orang atau obyek dalam
konteks referensi universal, sedangkan orientasi partikularistik berfokus pada
kategorisasi orang atau obyek secara spesifik.
3. Ketersebaran-keterkhususan.
Orientasi ini berfokus pada cara orang memberi respon pada orang lain.
Dengan orientasi ketersebaran, respon holistik akan diberikan seseorang
56
kepada orang lain, sedangkan orientasi keterkhususan ditampakkan seseorang
dengan memberi respon terhadap orang lain dalam cara yang khusus.
4. Askripsi-prestasi.
Orientasi askripsi dari seseorang akan tampak ketika orang tersebut
memandang orang lain. Dengan orientasi askriptif, pandangan seseorang akan
bertolak pada prediksi sosiokultural, yakni dalam kerangka keanggotaan orang
lain di dalam kelompoknya, seperti jender, umur, ras, etnik, kasta, dan
sebagainya. Sementara orang dengan orientasi prestasi akan mendasarkan
prediksi dalam kerangka prestasi yang dapat diraih orang lain.
5. Orientasi instrumental-ekspresif.
Orientasi instrumental ditampakkan oleh orang dalam interaksinya dengan
orang lain jika interaksi itu merupakan sarana untuk mencapai tujuan lainnya,
sedangkan orientasi ekspresif akan tampak pada orang yang interaksinya
dengan orang lain merupakan tujuannya.
3.3. Penentuan Populasi dan Sampel
3.3.1. Ukuran Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Dalam
penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah para pegawai dan jajaran
manajemen yang bekerja di perusahaan multi nasional PT. Semarang Garment.
57
3.3.2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut (Sugiyono, 2008). Pelaksanaan wawancara mendalam pada
penelitian kualitatif memerlukan waktu cukup lama dan menggali informasi
secara detail, sehingga sampel yang digunakan biasanya dalam jumlah yang
terbatas. Untuk mendapat informan kunci yang tepat sesuai fokus penelitian, maka
informan diambil berdasarkan purposive sampling (pengambilan sampel sesuai
kebutuhan). Dengan dasar sampel yaitu jajaran manajer ekspatriat berkebudayaan
Korea dan karyawan lokal Indonesia pada PT. Semarang Garment Indonesia yang
paham kepemimpinan, sering berinteraksi dengannya atau merasakan
kepemimpinannya langsung, sudah bekerja PT. Semarang Garment Indonesia
minimal tiga tahun, serta bisa berbicara atau menjawab wawancara secara akurat.
Peneliti akan melakukan deteksi dini terhadap pemilihan sampel yang akurat
dengan penelusuran personal, misalnya mengajukan beberapa pertanyaan sesuai
kondisi nantinya, bersifat fleksibel.
Sumber informasi dalam penelitian akan diambil baik dari data primer
maupun sekunder. Dengan dasar kriteria di atas, peneliti menetapkan Sumber
Informasi Kunci (Key Informan), yaitu jajaran manajer ekspatriat PT. Semarang
Garment yang terdiri dari 3 orang manajer berkebangsaan dan berlatar belakang
budaya nasional Korea. Sumber Informasi Penunjang (Supportive Informan), yang
terdiri 7 orang karyawan perusahaan dengan latar belakang budaya lokal dan telah
bekerja minimal lima tahun di perusahaan tersebut.
Sementara penulis menetapkan sampel dalam penelitian ini hanya mengambil
orang –orang tersebut yang didasarkan dari adanya justifikasi sebagai berikut:
58
1. Jajaran manajer ekspatriat dengan latar belakang budaya Korea dimana
merupakan orang-orang yang melakukan kepemimpinan pada PT. Semarang
Garment karena mereka merupakan narasumber kunci.
2. Karyawan perusahaan PT. Semarang Garment dengan latar belakang budaya
lokal, untuk mengetahui implikasi kepemimpinan gaya Korea di PT.
Semarang Garment Indonesia.
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling, yaitu
pengambilan sampel sesuai kebutuhan yang sifatnya fleksibel, berdasar deteksi
awal peneliti terhadap kondisi responden sebagai sampel itu dan harus
representative mewakili populasi yang akan diteliti. Namun, harus sesuai dengan
patokan yang ditetapkan sebelumnya perihal posisi dan latar belakang budaya
nasionalnya di dalam perusahaan PT. Semarang Garment.
3.4. Jenis dan Sumber Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:
a. Data Primer
Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama
oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel untuk tujuan spesifik studi (Sekaran,
2006). Data ini berkaitan langsung dengan informan. Dalam penelitian ini, data
primer berupa data dari wawancara dengan karyawan pada PT. Semarang
Garment.
59
b. Data Sekunder
Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber
yang telah ada (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini, data sekunder berupa data
dari pihak internal baik yang dikumpulkan secara terpusat oleh perusahaan atau
dikumpulkan oleh komponen karyawan perusahaan, serta dari pihak eksternal
yang telah mengumpulkan dan mungkin mengalihkannya, yaitu dokumen foto,
CD, file dokumen digital, buku, artikel, dan lain-lain.
3.5. Metode Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah:
a. Studi Kepustakaan
Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan atau
referensi lain yang diterbitkan secara umum yang berkaitan dengan penelitian
gaya kepemimpinan dan penerapan manajemen.
b. Wawancara (Interview)
Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain
berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Peneliti dapat
memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya
melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diwawancara dan dapat melakukan
klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui. Hal pertama yang akan menjadi
perhatian peneliti saat melakukan interview adalah pihak yang harus
diwawancara. Untuk memperoleh data yang kredibel maka interview harus
60
dilakukan dengan Knowledgeable Respondent yang mampu menceritakan
dengan akurat kasus yang diteliti.
Hal kedua yang akan menjadi perhatian peneliti adalah membuat
responden mau bekerja sama baik dengan peneliti. Untuk merangsang pihak
lain mau meluangkan waktu untuk diinterview, maka perilaku pewawancara
dan responden harus selaras sesuai dengan perilaku yang diterima secara sosial,
sehingga ada kesan saling menghormati. Selain itu, interview harus dilakukan
dalam waktu dan tempat yang sesuai sehingga dapat menciptakan kenyamanan.
Data yang diperoleh dari wawancara umumnya berbentuk pernyataan yang
menggambarkan pengalaman, pengetahuan, opini dan perasaan pribadi. Untuk
memperoleh data ini, peneliti menggunakan metode wawancara standar yang
terskedul (Schedule Standardised Interview), interview standar tak terskedul
(Non Schedule Standardised Interview) atau interview informal (Non
Standardised Interview). Ketiga pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan
teknik sebagai berikut: (a) Sebelum wawancara dimulai, memperkenalkan diri
dengan sopan untuk menciptakan hubungan baik. (b) Menunjukkan bahwa
responden memiliki kesan bahwa dia orang yang “penting”. (c) Menggali data
sebanyak mungkin. (d) Tidak mengarahkan jawaban. (e) Mengulangi
pertanyaan jika perlu. (f) Mengklarifikasi jawaban. (g) Mencatat interview
(Chariri, 2007).
Wawancara sebagai proses interaksi antara peneliti dengan informan
mempunyai peranan penting dalam penelitian kualitatif. Oleh sebab itu, teknik
wawancara yang akan peneliti lakukan tidak dengan suatu struktur yang ketat,
melainkan secara longgar, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
61
bersifat terbuka sehingga dapat diperoleh informasi yang lengkap dan
mendalam. Kelonggaran ini senantiasa memberi kesempatan kepada informan
untuk dapat memberikan jawaban secara bebas dan jujur. Wawancara semacam
ini dapat pula disebut sebagai indepth interviewing. Dengan teknik wawancara
ini akan mendorong terciptanya hubungan baik antara peneliti dengan informan
sehingga sangat membantu dalam upaya memperoleh informasi. Tujuan
wawancara adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kepemimpinan
gaya Korea yang diterapkan di PT. Semarang Garment, hubungan antara
jajaran manajer ekspatriat dengan karyawan atau pekerja lokal, dan beberapa
hal lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.
c. Participant Observation
Adapun tujuan observasi ini adalah untuk memperoleh data mengenai
penerapan model kepemimpinan lintas budaya di perusahaan PT. Semarang
Garment, dan keefektifan kepemimpinan tersebut, yang dilihat dari penilaian
orang-orang di sekitarnya yang dipadukan dengan referensi ilmiah yang ada.
d. Telaah Organisational Record
Metode pengumpulan data ini bisa mendukung data dari observasi dan
interview. Selain itu, telaah terhadap catatan organisasi dapat memberikan data
tentang konteks historis setting organisasi yang diteliti. Arsip dan catatan
organisasi merupakan bukti unik dalam studi kasus, yang tidak ditemui dalam
interview dan observasi. Sumber ini merupakan sumber data yang dapat
digunakan untuk mendukung data dari observasi dan interview. Selain itu,
telaah terhadap catatan organisasi dapat memberikan data tentang konteks
62
historis setting organisasi yang diteliti. Sumber datanya dapat berupa catatan
adminsitrasi, surat-menyurat, memo, agenda, dan dokumen lain yang relevan.
3.6. Metode Analisis Data
3.6.1. Uji Reliabilitas dan Validilitas
Dalam penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas sering dinamakan
Kredibilitas. Case Study (dasar penelitian kualitatif) memiliki dua kelemahan
utama: (a) Peneliti tidak dapat seratus persen independen dan netral dari research
setting; (b) Case Study sangat tidak terstruktur (messy) dan sangat interpretive.
Dalam Moleong (2007) menawarkan beberapa prosedur untuk meningkatkan
kredibilitas penelitian kualitatif, yaitu triangulation, disconfirming evidence,
research reflexivity, member checking, prolonged engagement in the field,
collaboration, the audit trail, thick and rich description dan peer debriefing.
Dalam peningkatan kredibilitas penelitian ini, maka peneliti memilih prosedur
triangulation. Prosedur ini dipilih karena disesuaikan dengan fokus penelitian
kualitatif yang dilakukan, yang berdasarkan case study dimana peneliti merupakan
instrument riset utama.
Prosedur triangulasi yaitu menggunakan berbagai pendekatan dalam
melakukan penelitian. Maksudnya, peneliti dapat menggunakan berbagai sumber
data, teori, dan metode agar informasi yang disajikan konsisten. Oleh karena itu,
untuk memahami dan mencari jawaban atas pertanyaan penelitian, peneliti dapat
mengunakan lebih dari satu teori, lebih dari satu metode (inteview, observasi dan
analisis dokumen). Di samping itu, peneliti melakukan interview manajer Korea
menginterpretasikan temuan dengan pihak lain, yaitu karyawan lokal.
63
3.6.2. Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pendekatan tunggal dalam analisis
data. Pemilihan metode sangat tergantung pada pertanyaan penelitian dan
kerangka penelitian yang mendasari penelitian. Untuk melakukan analisis, peneliti
menangkap, mencatat, menginterpretasikan dan menyajikan informasi. Satu hal
yang menjadi perhatian peneliti adalah analisis data ini tidak dapat dipisahkan dari
data collection. Oleh karena itu, ketika data mulai terkumpul dari nara sumber,
observasi dan literatur atau data pendukung, analisis data harus segera dilakukan
untuk menentukan pengumpulan data berikutnya. Adapun langkah analisis dapat
dilakukan sebagai berikut (Chariri, 2007):
a. Data Reduction
Intinya, mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat
diproses ke langkah selanjutnya. Ini karena data masih mentah, jumlahnya sangat
banyak, dan bersifat non-kuantitatif (sangat deskriptif) sehingga tidak dapat
digunakan secara langsung untuk analisis. Data reduction mencakup kegiatan
berikut ini:
1. Organisasi Data (Menentukan Kategori, Konsep, Tema, dan Pola atau
Pattern)
Data dari interview akan ditulis penulis lengkap dan dikelompokkan
menurut format tertentu (misal menurut jabatan struktural). Dengan cara ini,
peneliti dapat mengidentifikasi informasi sesuai pemberi informasi dengan
misalnya jabatan responden. Transkrip hasil interview kemudian dianalisis dan
key points akan ditandai untuk memudahkan coding dan pengklasifikasian.
Sedangkan data dari observasi dan arsip akan berupa catatan (field note).
64
Prosesnya tidak berbeda jauh dengan data hasil wawancara. Field note selama
observasi, diorganisir ke dalam form dengan judul tertentu, seperti tanggal,
jam, peristiwa, partisipan, deskripsi peristiwa, dimana terjadinya, bagaimana
terjadi, apa yang dikatakan, serta opini dan perasaan peneliti. Sementara itu,
data dari analisis catatan organisasi (arsip), diorganisir ke dalam format
tertentu untuk mendukung data dari observasi dan interview.
2. Coding Data
Data yang diperoleh dari langkah di atas, kemudian dikelompokkan ke
dalam tema tertentu dan diberi kode untuk melihat kesamaan pola temuan.
Coding harus dilakukan sesuai dengan kerangka teoritis yang dikembangkan
sebelumnya. Dengan cara ini, Coding memungkinkan peneliti untuk
mengkaitkan data dengan masalah penelitian.
3. Pemahaman (understanding) dan Mengujinya
Atas dasar coding, peneliti akan memulai memahami data secara detail dan
rinci. Proses ini dapat berupa “pemotongan” data hasil interview dan
dimasukkan ke dalam folder khusus sesuai dengan tema/pattern yang ada.
Hasil observasi dan analisis dokumen akan dimasukkan ke dalam folder yang
sama untuk mendukung pemahaman atas data hasil interview. Data kemudian
dicoba dicari maknanya/diinterpretasi. Dalam melakukan interpretasi, peneliti
berpegang pada koherensi antara temuan interview, observasi, dan analisis
dokumen.
b. Interpretasi
Hasil interpretasi kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga
interpretrasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut. Untuk
65
memudahkan analisis, peneliti akan menggunakan strtaegi dibawah ini, merujuk
dari Nuemen (2003):
1. Narrative (menceritakan secara detail kejadian dalam setting)
2. Ideal types (membandingkan data kualitatif dengan model kehidupan sosial
yang ideal)
3. Success approximation (mengkaitkan data dengan teori secara berulang-
ulang, sampai perbedaannya hilang)
4. Illustrative method (mengisi “kotak kosong” dalam teori dengan data
kualitatif)
5. Path Dependency and Contingency (memulai dengan hasil kemudian
melacak balik urutan kejadian untuk melihat jalur yang menjelaskan
kejadian tersebut)
6. Domain analysis (memasukkan istilah-istilah asli yang menunjukkan ciri
khas obyek yang diteliti)
7. Analytical Comparison (mengidentifikasi berbagai karakter dan temuan
kunci yang diperoleh, membandingkan persamaan dan perbedaan karakter
tersebut untuk menentukan mana yang sesuai dengan temuan kunci).
c. Triangulasi
Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari
berbagai sumber. Menurut Institute of Golbal Tech dijelaskan bahwa Triangulasi
mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir
dan meningkatkan kebijakan serta program yang berbasis pada bukti yang telah
tersedia.
66
Dengan cara menguji informasi dengan mengumpulkan data melalui metode
berbeda, oleh kelompok berbeda dan dalam populasi berbeda, penemuan mungkin
memperlihatkan bukti penetapan lintas data, mengurangi dampaknya dari
penyimpangan potensial yang bisa terjadi dalam satu penelitian tunggal.
Triangulasi menurut Susan Stainbackdalam Sugiyono (2007:330) merupakan
“the aim is not to determinate the truth about same social phenomenon, rather
than the purpose oftriangulation is to increase one’s understanding of what ever
is being investigated.” Dengan demikian triangulasi bukan bertujuan mencari
kebenaran, tapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang
dimilikinya.
Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan
data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan
hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330)
Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda
(Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini
selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk
memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna
untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi
bersifat reflektif.
Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi
diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan
teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya
menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber.
67
Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang
berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton,1987:331). Adapun untuk mencapai
kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang
dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat
dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the
data according to the convergence of multiple data sources or multiple data
collection procedures (Wiliam Wiersma,1986). Triangulasi dalam pengujian
kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan
berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber,
triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.
Penjelasan Triangulasi diatas sebagai berikut :
1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh,
untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka
pengumpulan dan pengujian adata yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan
68
yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan
kelompok kerjasama. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan
seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana
pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga
sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga
menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga
sumber data tersebut.
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan
cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi,
dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data
tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi
lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain. Atau mungkin
semua benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.
3. Triangulasi Waktu
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan
dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum
banyak masalah, sehingga akan memberikan data yang lebih valid dan lebih
kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan
dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik
lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang
berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan
kepastian datanya.
69
Triangulasi juga dapat dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari
peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.
3.7. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
A. Persiapan
Dalam tahapan awal penelitian ini, peneliti melakukan beberapa langkah
untuk membantu jalannya proses penelitian sebagai berikut :
a. Penyusunan Proposal.
b. Pengurusan Izin Penelitian.
c. Pemilahan Informasi Penelitian.
d. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.
e. Pengembangan Pedoman Pengumpulan Data.
B. Penelitian Lapangan
Dalam tahap penelitian lapangan, guna memenuhi kebutuhan data
penelitian, peneliti melakukan langkah-langkah berikut ini :
a. Memulai penelitian lapangan dengan benar dengan membekali diri terlebih
dahulu dari berbagai literatur.
b. Menentukan research setting.
c. Memasuki research site.
d. Melakukan sikap yang akomodatif ketika di research site.
e. Observasi dan pengumpulan data (mengembangkan sikap melihat dan
mendengar, serta taking notes).
f. Memfokuskan pada setting khusus.
g. Melakukan Field Interviews.
70
C. Menganalisis Data
Setelah pencarian data dirasa cukup dan sudah memenuhi kebutuhan untuk
dilakukan analisis maka langkah analisis data akan dilakukan peneliti dengan
urutan langkah berikut ini :
a. Melakukan analisis awal apabila data yang terkumpul telah memadai.
b. Mengembangkan reduksi data temuan.
c. Melakukan analisis data temuan.
d. Mengadakan pengayaan dan pendalaman data.
e. Melakukan interpretasi data berdasar teori yang ada.
f. Merumuskan kesimpulan akhir.
g. Menyiapkan penyusunan laporan penelitian dan menguji keabsahan data.
D. Penyusunan Laporan Penelitian
Setelah proses analisis data selesai dilakukan, dan diperoleh data yang
valid dan reliabel (kredibel), maka peneliti akan melakukan proses akhir dari
penelitian, yaitu menyusun laporan penelitian. Adapun langkah-langkah yang
ditempuh dalam menyusun laporan penelitian adalah sebagai berikut:
a. Prewriting (mengatur catatan atau literatur, membuat daftar ide, outlining,
melengkapi kutipan dan mengorganisasi komentar pada data analisis).
b. Composing (menuangkan ide dalam kertas sebagai draft pertama, dengan
memperhatikan kutipan, menyiapkan data untuk penyajian, serta membuat
pengantar dan konklusi).
c. Rewriting (mengevaluasi dan “memoles” laporan dengan memperbaiki
koherensi, proofreading atas salah tulis, mengecek kutipan, mengkaji kembali
style dan tone tulisan).
71
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
STUDI LINTAS BUDAYA
KEPEMIMPINAN GAYA KOREA DI INDONESIA
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1. Gambaran Umum PT. Semarang Garment
PT. Semarang Garment merupakan perluasan usaha dari perusahaan
internasional Kukdong Corporation yang berpusat di Seoul, Korea Selatan. Selain
PT. Semarang Garment, PT. Kukdong Corporation (sebagai head office) telah
memiliki perluasan usaha di Bekasi Jawa Barat, Indonesia tepatnya di Desa
Cikiwul, Bantar Gebang serta beberapa negara lain seperti Amerika Serikat dan
Meksiko. Untuk America Office, kantornya berlokasi di Wilshire Blvd, Los
Angeles. Sementara Mexico Office & Factory berlokasi di Rancho Los Soles
Atlico De Puebla, Mexico. PT. Semarang Garment sendiri terletak di wilayah
Desa Wujil Bergas, Kabupaten Semarang. Perusahaan tersebut memiliki 2572
karyawan. Di dalam perusahaan, mereka menempatkan pimpinan serta jajaran
manajer ekspatriat yang berasal dari negaranya yaitu Korea Selatan dan para
pemimpin ini membawahi sejumlah karyawan yang merupakan penduduk lokal.
Perusahaan yang memiliki luas area (factory site) kurang lebih 30.000 m2
dengan luas bangunan (factory building) 22.000 m2
tersebut bergerak di bidang
industri garment dan berdiri di Kabupaten Semarang sejak bulan September 2003.
Total produksi pakaian jadi yang dihasilkan dalam perusahaan tersebut kurang
72
lebih 700.000 pieces per bulannya. Negara tujuan eksport dari PT. Semarang
Garment antara lain Perancis, Jerman, Benelux, Inggris, Spanyol, Italia, Denmark,
Belanda, Australia, Jepang, dan Amerika. Produksi pakaian jadi yang telah siap
dikemas akan didistribusikan pada konsumer utama (main customers) seperti
Nike, Columbia, H&M, Walmart, Hema, D&D, Daiz, Elcorte Ingles, VF
Imagewear dan beberapa pembeli (buyer) lainnya.
4.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan
PT. Semarang Garment memiliki dua buah factory pada satu area yang
sama. Perusahaan yang dipimpin langsung oleh seorang pimpinan yang juga
sebagai pemilik perusahaan yaitu Byun Hyo Su, berkebangsaan Korea Selatan dan
telah mengembangkan usahanya ke beberapa negara di dunia ini mempekerjakan
1451 karyawan pada factory I dan sejumlah 1121 karyawan pada factory II
sehingga total karyawan keseluruhan adalah 2572 orang yang merupakan
penduduk lokal. Struktur organisasi perusahaan yang terdapat pada PT. Semarang
Garment terdiri dari tiga struktur organisasi yang merupakan bagian dari
perusahaan, dimana terdapat struktur organisasi pada kantor (office) dan struktur
organisasi pada factory pertama dan factory kedua. Keseluruhan struktur
organisasi yang ada menggambarkan tatanan organisasi pada PT. Semarang
Garment.
73
Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Semarang Garment 2013
A. Struktur Organisasi Office
Sumber : Hasil Observasi Peneliti, 2013
76
4.1.3. Lokasi Perusahaan
Perusahaan yang bergerak di bidang industri garmen ini telah beroperasi
kurang lebih sepuluh tahun di Kabupaten Semarang. Lokasi PT. Semarang
Garment sendiri tepatnya berada pada :
Jalan : Jl. Soekarno Hatta Km.25
Desa : Desa Wujil
Kecamatan : Kecamatan Bergas
Kabupaten : Semarang
Propinsi : Jawa Tengah
Negara : Indonesia
Lokasi tersebut merupakan area yang telah disetujui untuk kegiatan
industri dan telah terdaftar serta mendapat sertifikasi dari pemerintah sebagai
lokasi untuk kegiatan operasional industri.
PT. Semarang Garment memiliki area dengan luas wilayah 30.000 m2
dimana terdapat bangunan untuk kantor (office), factory I dan factory II, serta
terdapat rumah inap (mess) bagi karyawan ekspatriat dari Korea Selatan dan
berbagai fasilitas pendukung operasional pabrik. Semuanya terletak pada satu
komplek yang sama, yaitu di area PT. Semarang Garment.
4.1.4. Aktivitas dalam Perusahaan Semarang Garment
Setiap perusahaan menjalankan aktivitas untuk mendukung operasional
perusahaan tersebut. PT. Semarang Garment memiliki berbagai kegiatan yang
dilakukan untuk menghasilkan produk dan manajemen dalam perusahaan sendiri.
77
4.1.4.1. Aktivitas Produksi
Berbagai kegiatan terjadi pada perusahaan, khususnya untuk mendukung
proses produksi. Perusahaan yang bergerak di bidang industri garmen ini memiliki
kegiatan produksi sebagai berikut :
Gambar 4.2
Proses Produksi pada PT. Semarang Garment
Sumber : Hasil observasi peneliti, 2013
Proses produksi dimulai dengan barang (bahan baku) yang datang
disimpan dalam gudang atau penyimpanan. Setelah itu disusun sebuah sample
yang akan disetujui oleh pusat dan dikonsultasikan dengan buyer. Jika telah
didapat sample yang dibutuhkan, akan masuk ke tahap autocad yaitu
penggambaran desain pasti yang akan digunakan sebagai acuan pembuatan
produk. Selanjutnya melalui proses cutting, printing¸ embroidery (jika diperlukan
materi atau produk yang berbordir) selanjutnya ke tahap penjahitan (sewing).
Setelah berupa pakaian jadi akan masuk ke tahap pengecekan (quality control)
Gudang Cutting
Embroidery
Sample Autocad
QC Printing Sewing
Ironing Packing Gudang Finishing
Spot Cleaning
Export
78
untuk dilihat dan ditinjau mengenai kualitas produk dan selanjutnya spot cleaning
hingga ironing. Setelah produk siap semuanya akan dilanjutkan ke tahap
pengemasan (packing) dan masuk ke gudang (finishing) sebelum pada akhirnya
akan diekspor.
Gambar 4.3
Beberapa Kegiatan Produksi Perusahaan PT. Semarang Garment
Sewing Department Embroidery Department
Warehouse Departement Cutting Department
Finishing Sumber : Hasil observasi peneliti, 2013
79
4.1.4.2. Aktivitas Pelatihan (Training)
Selain kegiatan produksi, juga terdapat kegiatan pelatihan pada PT.
Semarang Garment yang dilakukan secara berkala. Diantaranya terdapat pelatihan
terhadap karyawan yang merupakan fungsional perusahaan sebagai penjaga
keamanan (security) yaitu berupa pelatihan terkait dengan pengamanan di
lingkungan perusahaan. Selain itu juga terdapat pelatihan bagi karyawan baru
yang akan bergabung sebagai tenaga penjahit, pembordir, maupun tenaga untuk
desain di bagian autocad dan lainnya. Bagi karyawan yang telah bekerja di PT.
Semarang Garment juga memperoleh pelatihan mengenai abuse & harrasment
atau pelecehan dan kekerasan yang mungkin terjadi pada lingkungan kerja. Hal ini
dilakukan untuk upaya mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan pada
lingkungan kerja di PT. Semarang Garment.
Pelatihan lain yang juga diberikan pada karyawan di PT. Semarang
Garment antara lain, pelatihan menganai sistem pinjaman atau lean system, juga
pelatihan mengenai sistem gaji yang diterapkan di PT. Semarang Garment
(payroll system) serta berbagai pelatihan lain untuk mencegah keamanan,
kenyamanan serta kelancaran para karyawan dalam melakukan pekerjaan di PT.
Semarang Garment.
Keseluruhan pelatihan yang diberikan pada karyawan merupakan bentuk
pelatihan yang meningkatkan kemampuan atau keahlian karyawan serta pelatihan
untuk mengamankan diri dan menjadikan suasana kerja lebih nyaman serta
bertujuan untuk melancarkan kegiatan operasional perusahaan.
80
Gambar 4.4
Beberapa Kegiatan Pelatihan PT. Semarang Garment
EVACUATION DRILL FIRE DRILL
TRAINING PAYROLL SYSTEM TRAINING ABUSE AND HARASSMENT
TRAINING LEAN SYSTEM TRAINING CTPAT
Sumber : Hasil observasi peneliti, 2013
81
4.1.4.3. Aktivitas Penunjang Lainnya
PT. Semarang Garment juga memiliki kegiatan di dalam manajemen
perusahaan, seperti rapat rutin komitte, rapat komitte HSE, rapat dan pelatihan
dengan buyer. Selain itu, secara berkala akan ada kunjungan dan rapat dengan
pihak pemerintah dan kegiatan sertifikasi tertentu bagi perusahaan. Ketika tiba
waktunya peringatan hari buruh, juga terdapat acara yang diadakan perusahaan
bagi seluruh karyawan sebagai bentuk apresiasi perusahaan atas kinerja seluruh
karyawan selama bekerja di PT. Semarang Garment.
Gambar 4.4
Beberapa Kegiatan Lain PT. Semarang Garment
Bipartite Comitte Meeting & Training with Buyer
Government Visitation & Training
Human Right Celebration Day
Sumber : Hasil observasi peneliti, 2013
82
4.1.5. Produk PT. Semarang Garment
PT. Semarang Garment bergerak di bidang industri garmen dan telah
menjalankan usahanya di Semarang selama sepuluh tahun. Perusahaan ini
memiliki capital (paid up) sebesar US $ 2.000.000; dan line produksi sebanyak 33
sewing lines yqng terdiri dari 17 lines pada factory I dan 15 lines pada factory II.
Jumlah keseluruhan mesin yang digunakan untuk kegiatan produksi sebanyak
1447 mesin jahit (sewing machines) dengan 15 mesin komputer pembordiran.
Total produktivitas yang dilakukan pada PT. Semarang Garment kurang
lebih 700.000 pieces per bulan. Item-item yang diproduksi pada perusahaan ini,
antara lain knit sweat shirt, training suits, pants, polo shirts, T-shirts, dress skirtts,
cardigan, overall, lycra pants, body suit, dan night wear (pyjamas, night gown).
Produk-produk yang telah selesai diproduksi dan dikemas selanjutnya
akan diekspor ke negara-negara seperti Perancis, Jerman, Benelux, Inggris,
Spanyol, Italia, Denmark, Belanda, Australia, Jepang dan Amerika.
4.1.6. Kondisi Lingkungan Kerja pada Office PT. Semarang Garment
PT. Semarang Garment memiliki wilayah yang cukup luas namun
sebagian besar wilayahnya digunakan untuk kegiatan operasional pabrik.
Sementara ruang-ruang yang digunakan untuk kantor hanya sebagian kecil
wilayah dari keseluruhan bangunan di area Semarang Garment. Staff office yang
bekerja pada PT. Semarang Garment berjumlah 34 orang dan merupakan
karyawan lokal. Terdapat dua lantai yang merupakan bangunan office dan tempat
karyawan melakukan pekerjaannya. Lantai pertama digunakan untuk administrasi,
ruang autocad dan klinik kesehatan. Sementara lantai kedua digunakan untuk
83
kantor bagi staff yang lain. Terdapat pula ruangan bagi pimpinan utama
perusahaan, wakil pimpinan dan beberapa ruangan manajer, serta sebuah ruang
rapat atau meeting yang digunakan untuk rapat berkala dan menerima tamu-tamu
dari instansi tertentu pada lantai kedua tersebut. Bangunan yang digunakan untuk
office ini terletak di bagian depan dari area Semarang Garment dan terhubung
langsung dengan pabrik, tempat produksi. Pada kantor ini juga terdapat beberapa
pintu dan jendela yang langsung menghubungkan dengan pabrik sehingga kondisi
pabrik dan setiap aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi dapat dilihat
secara langsung melalui jendela-jendela yang mengarah pada ruang-ruang
operasional di pabrik.
Terdapat beberapa pajangan dinding yang menghiasi sepanjang ruangan
yang digunakan untuk kantor tersebut. Diantaranya terdapat poster-poster
mengenai pedoman dalam berperilaku bagi karyawan maupun bagi pihak
manajemen yang dikeluarkan oleh Nike, Inc. yang merupakan buyer utama dari
PT. Semarang Garment.
Selain beberapa hal tersebut, PT. Semarang Garment juga memberikan
peringatan terhadap daerah atau area berbahaya tertentu dengan menggunakan tiga
bahasa, diantaranya bahasa Korea, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hal ini
terjadi pula pada kalimat mutiara yang terdapat tidak hanya pada satu ruangan,
tetapi terdapat hingga tiga buah pajangan sejenis di sepanjang kantor dimana
menyerukan kalimat “Orang rajin selalu mencari cara, orang malas selalu mencari
alasan.” Terdapat tiga bahasa dalam setiap pajangan yang ditempelkan pada sisi
ruangan tertentu pada kantor tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat
tersebut menjadi kalimat yang dipegang oleh diri mereka sendiri dan
84
mengharapkan karyawan lain mengikuti pemikiran yang demikian. Kerajinan dan
semangat kerja sangat penting bagi orang Korea, khususnya para manajer dan
pimpinan yang berada di PT. Semarang Garment.
Pada dinding kantor juga terpajang beberapa foto pimpinan beserta wakil
pimpinan dengan seluruh jajaran manajer ekspatriat yang berkebangsaan Korea
dan piagam serta sertifikat yang diberikan oleh perusahaan buyer yang telah
bekerjasama dengan PT. Semarang Garment.
Ruangan pimpinan yang menyatu dengan bawahan juga ditemukan pada
PT. Semarang Garment. Ruang khusus hanya diadakan untuk pimpinan utama
atau presiden direktur dan wakil pimpinan atau wakil presiden direktur PT.
Semarang Garment. Untuk para manajer ruangan yang dimiliki terkesan menyatu
dengan karyawan (staff) lain namun deng space atau area yang sedikit lebih luas.
Tidak terdapat penyekat khusus antara ruang manajer dengan karyawan atau staff
yang lain.
Pada kantor tersebut hanya terdapat satu ruang rapat atau pertemuan yang
memiliki jendela-jendela yang langsung menghadap pada pabrik, tempat produksi.
Pada ruang pertemuan ini terdapat beberapa display dari sample produk yang siap
didistribusikan pada buyer, antara lain untuk Nike, Columbia, H&M, Walmart,
Hema, D&D, Daiz, Elcorte Ingles dan VF Imagewear.
Para manajer pabrik, untuk factory I maupun factory II memiliki ruangan
khusus yang terletak pada pabrik atau factory dan tidak memiliki ruangan khusus
di kantor atau office tersebut.
85
Gambar 4.5
Kondisi Lingkungan Office
Sumber: Hasil observasi peneliti, 2013
Ruangan manajer yang tidak terpisah dengan staff; Ruang pertemuan dengan display
sample produk dan jendela yang langsung menghadap ke pabrik, tempat produksi.
Serifikat dan piagam dari perusahaan buyer; kalimat mutiara sebagai filosofi kerja;
karyawan teladan 2012; peringatan; dan pedoman perilaku oleh Nike, Inc.
86
4.2. Pembahasan
Guna melengkapi penelitian mengenai kepemimpinan lintas budaya
khususnya kepemimpinan gaya Korea di Indonesia ini selain melakukan
observasi, menerangkan perilaku yang terlihat dan lingkungan fisik serta mencatat
gejala atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian, tetapi juga
memperhatikan makna dari hal-hal tersebut bagi karyawan di perusahaan tersebut.
Untuk mengetahui kepemimpinan lintas budaya, khususnya
kepemimpinan gaya Korea di Indonesia pada PT. Semarang Garment, diperlukan
teknik pengumpulan data dengan dokumentasi berbagai bentuk data yang
dibutuhkan sebagai pendukung penelitian kualitatif. Analisis data terkait
kepemimpinan gaya Korea di Indonesia pada penelitian ini mengacu kerangka
pikir penelitian dan literatur yang mendukung. Mengenai sumber untuk mengkaji
kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh
melalui beberapa sumber. Dalam hal ini, guna menguji kredibilitas data tentang
gaya kepemimpinan Korea di Indonesia, dilakukan terhadap bawahan yang
dipimpin dan merupakan karyawan lokal dari Indonesia.
4.2.1. Profil Narasumber
Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap objek
penelitian yang merupakan karyawan pada PT. Semarang Garment. Para
narasumber terdiri dari manajer ekspatriat perusahaan yang berasal dari Korea
Selatan dan karyawan lokal yang diantaranya adalah karyawan yang berhubungan
langsung dengan manajer ekspatriat, pekerja pabrik, hingga cleaning service dan
security yang merupakan penduduk lokal Indonesia pada PT. Semarang Garment
87
dengan masa kerja minimal 3 tahun. Terdapat jumlah total 10 narasumber untuk
penelitian kepemimpinan gaya Korea di PT. Semarang Garment.
Tabel 4.1
Daftar Nama Narasumber
Kode Nama Narasumber Jabatan/Divisi Masa Bekerja
R1 Kim Hak Hee
(Richard Kim)
Manager of
Factory I
5 tahun
R2 Byun Sang In General Manager,
Acc. Manager, Ex-
Im Manager
10 tahun
R3 Park Tae Seon Finishing
Manager
10 tahun
R4 Tri J. M/ Labor concern 5 tahun
R5 Ambar Sample Chief 5 tahun
R6 Hernowo Finishing Chief 8 tahun
R7 Endang S. Worker 5 tahun
R8 Winarni Worker 6 tahun
R9 Rini Cleaning service 10 tahun
R10 Hertanto Security 10 tahun
4.2.2. Analisis dan Keabsahan Data
Dalam menguji keabsahan data penelitian menggunakan teknik triangulasi.
Menurut lexy J. Moleong (2007) triangulasi adalah bentuk pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
Denzin (1978) dalam Lexy J. Moleong (2007) membedakan empat macam
triangulasi sebagai teknik pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data yang
memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori yang mendukung.
Triangulasi dilakukan dengan wawancara, observasi langsung, observasi
tidak langsung. Observasi tidak langsung ini dimaksudkan untuk melakukan
88
pengamatan beberapa kajian agar diperoleh kemudahan dalam mencari titik temu
yang menghubungkan diantara kejadian tersebut. Teknik pengumpulan data yang
digunakan untuk melengkapi dalam memperoleh data primer dan sekunder.
Observasi dan interview digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan
dengan kepemimpinan gaya Korea di Indonesia.
4.2.3. Persepsi Pimpinan (Manajer) dan Karyawan
Dalam proses penelitian ini juga dilakukan analisis terhadap persepsi
pimpinan pada bawahannya serta persepsi bawahan terhadap pimpinannya dimana
terdapat perbedaan budaya antara kelompok pimpinan yang merupakan manajer
ekspatriat Korea dengan bawahan yang merupakan penduduk lokal Indonesia.
Setelah dilakukan pengumpulan dan reduksi data yang diperoleh dari hasil
wawancara dengan narasumber dan pengamatan lokasi dapat dianalisis mengenai
persepsi pimpinan terhadap bawahan begitu pula sebaliknya. Hal ini untuk
mendukung dan menguatkan hasil penelitian terkait kepemimpinan lintas budaya
khususnya kepemimpinan gaya Korea di Indonesia.
4.2.3.1. Persepsi Pimpinan (Manajer Ekspatriat Korea) terhadap
Karyawan
Manajer ekspatriat pada PT. Semarang Garment berasal dari Korea Selatan
dan kebanyakan dari mereka kurang mampu menggunakan bahasa Indonesia
maupun bahasa Inggris secara baik dan benar. Komunikasi terjalin dengan cukup
baik antara orang lokal dengan orang Korea khususnya terkait pekerjaan
meskipun mengalami kesulitan pada awalnya. Perbedaan budaya dan bahasa yang
terjadi antara karyawan lokal dengan atasannya yang berkebangsaan Korea
89
menimbulkan persepsi tersendiri bagi pimpinan, yaitu para manajer dari Korea
terhadap bawahannya yang merupakan karyawan lokal.
Para manajer memiliki anggapan tersendiri terhadap karyawan lokal di PT.
Semarang Garment. Penyesuaian yang cukup sulit dilakukan oleh manajer dari
Korea selama tahun-tahun awal mereka bekerja di perusahaan tersebut. Banyak
karyawan yang menurut mereka lamban dalam belajar dan bekerja juga sering
melakukan kesalahan. Hal ini bertentangan dengan sikap mereka yang rajin,
cekatan dan cepat dalam bekerja. Setelah berjalan beberapa tahun, seiring dengan
pelatihan dan pemahaman yang diberikan atasan pada karyawan, mereka mampu
bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik.
Ketiga narasumber (R1, R2 dan R3) yang merupakan manajer ekspatriat
Korea berpendapat bahwa karyawan lokal sempat membuat mereka tertekan pada
awal tahun mereka bekerja di PT. Semarang Garment. Pendapat ketiga
narasumber diwakili R1 sebagai berikut :
“Each persons have each characteristics. Some of them learn quickly, some of
them is doing something slowly. Some is good some is not good. The first two
years i worked here i often found employees which often late, not fast, slowly
learning, not working. And i got alot of headache because of that. But now,
i’m not really headache and stressful anymore, they become more skillful.”
Selain itu, mereka juga menganggap orang Indonesia sangat baik dan ramah
dan membuat orang asing seperti mereka merasa nyaman dan dihargai oleh
karyawan. Ketiga narasumber (R1, R2 dan R3) juga memiliki pendapat yang sama
mengenai hal ini. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan R3 yang mewakili ketiga
narasumber sebagai berikut :
“Orang Indonesia di sini baik dan ramah. Sudah tidak banyak masalah
dengan pekerjaan sekarang. Mereka sudah bekerja dengan baik. Kami
melatih dan membuat karyawan lebih baik.”
90
Dengan pernyataan dari ketiga narasumber yang sejenis, dapat diketahui
bahwa mereka sudah mulai mampu beradaptasi dengan orang Indonesia seiring
pelatihan yang diberikan pada mereka dan menjadikan mereka karyawan yang
lebih baik dalam persepsi manajer.
Satu hal yang sulit diubah dari kebanyakan karyawan Indonesia adalah
penggunaan waktu yang tidak efektif dan efisien dalam pekerjaan. Hal ini
ditunjukkan dengan pernyataan narasumber 1 (R1) dalam wawancara yang telah
dilakukan sebagai berikut :
“Do you know the sentences “jam karet Indonesia”? Exactly often happen.
Pasti ada jam karet. In Korea when working we have to do
“balii..balii..ballii..”. our boss will tell us to do so. Balli means do it faster
and faster. Tapi di sini daripada on time, mereka santai-santai. Besok ada
lagi besok ada lagi.”
Menurut para manajer, kebiasaan karyawan dari Indonesia seringkali
menunda pekerjaan sehingga terkesan lama dalam pengerjaan. Bagi mereka jika
terdapat sisa waktu, mereka dapat menggunakannya untu pekerjaan lain atau
segera beristirahat jika tidak ada lagi yang dikerjakan.
Perbedaan cara kerja antara manajer dan bawahan menimbulkan
penyesuaian dari kedua belah pihak dan akhirnya tidak terjadi masalah yang
berarti.
4.2.3.2. Persepsi Karyawan terhadap Pimpinan (Manajer Ekspatriat
Korea)
Karyawan yang dimaksud merupakan karyawan perusahaan yang
berkebangsaan Indonesia dan sebagian besar merupakan warga sekitar Ungaran,
khususnya daerah Kecamatan Bergas yang sangat dekat dengan PT. Semarang
Garment. Komunikasi terjalin dengan cukup baik antara orang lokal dengan orang
Korea khususnya terkait pekerjaan meskipun mengalami kesulitan pada awalnya.
91
Perbedaan budaya dan bahasa yang terjadi antara karyawan lokal dengan
atasannya yang berkebangsaan Korea menimbulkan persepsi tersendiri bagi
karyawan lokal terhadap manajernya yang berkebangsaan Korea, khususnya
Korea Selatan.
Para karyawan memiliki anggapan tersendiri terhadap manajer ekspatriat
dari Korea di PT. Semarang Garment. Penyesuaian yang cukup sulit dilakukan
oleh karyawan lokal dari Korea selama tahun-tahun awal mereka bekerja di
perusahaan tersebut. Menurut karyawan lokal, manajer mereka pada dasarnya
cukup baik dan ingin seluruh karyawannya mengusahakan yang terbaik bagi
perusahaan.
Menurut tiga narasumber (R4, R5 dan R6) mereka menganggap manajer
dari Korea cukup baik dan mengupayakan hal yang baik bagi karyawannya seperti
diwakili oleh pernyataan R4 sebagai berikut :
“Pada dasarnya mereka baik dan tidak memberikan kesulitan untuk kami
(bawahannya) saat bekerja. Ketika kita berbuat salah, selama kita tahu
kesalahan kita dan segera mengakui serta minta maaf, mereka akan sangat
menghargai itu.”
“...Mereka cenderung membatasi diri dan menjaga jarak antara atasan
dengan bawahan di lingkungan kerja dan sangat serius...”
Selain itu, menurut karyawan lokal, para manajer dari Korea cenderung
bersikap serius saat bekerja dan memilih untuk membatasi diri dengan karyawan.
4.2.4. Karakteristik Kepemimpinan Lintas Budaya Berdasarkan
Kluchkholn dan Strodtbeck serta Pola-Pola Parson
Pembahasan mengenai studi lintas budaya khususnya kepemimpinan gaya
Korea di Indonesia pada PT. Semarang Garment dibatasi dimensi-dimensi yang
spesifik untuk melihat secara mendalam mengenai kepemimpinan dengan latar
92
belakang budaya Korea di Indonesia. Dimensi tersebut merupakan dimensi
budaya Kluchkhon dan Stridtbeck serta pola-pola Parson yang mendukung telaah
teori penelitian ini. Selanjutnya akan dianalisis mengenai pandangan setiap
narasumber yang merupakan manajer dari Korea terhadap gaya kepemimpinan
dengan latar belakang budaya Korea yang mereka upayakan serta pandangan
karyawan lokal yang menerima gaya kepemimpinan tersebut. Hal ini dilakukan
untuk mendukung studi lintas budaya yang dilakukan oleh peneliti.
4.2.4.1. Dimensi Budaya Kluchkhon & Strotdbeck
Dalam studi ini, digunakan enam dimensi Kluchkhon dan Strotdbeck untuk
mengamati dan menganalisis kepemimpinan gaya Korea di Indonesia. Berikut
akan diberikan pembahasan secara lengkap.
1. Nature of humans (karakter dasar manusia)
Terdapat dua pandangan terhadap karakter dasar manusia. Karakter yang
dimaksud adalah sifat dasar yang melekat pada diri manusia. Dimana yang
pertama memandang manusia memiliki sifat baik dan buruk di dalam dirinya,
sementara yang kedua memandang manusia memiliki sifat yang dapat berubah
atau tidak dapat berubah sama sekali.
Berdasarkan simpulan hasil wawancara terhadap narasumber dapat
diketahui bahwa pandangan orang Korea meyakini manusia memiliki karakter
baik dan buruk di dalam dirinya. Pada dasarnya mereka terlahir sama, namun
lingkungan, pendidikan dan banyak faktor lain yang menentukan sifat mana yang
berkembang dalam dirinya serta akan menjadi orang yang bagaimana nantinya.
93
Ketiga narasumber (R1, R2 dan R3) yang merupakan manajer dari Korea
memberikan pernyataan yang sama dan ditunjukkan oleh salah satu dari mereka,
yaitu pernyataan R1 sebagai berikut :
“The philosophy in our country, there are two kind of characteres of human
which are good and bad. Basically human being is born the same. But how do
they grow, it’s depending on their surrounding, their education from home,
school and society that determine what kind of person he will be.”
Pernyataan tersebut juga dibenarkan dan telah divalidasi oleh pernyataan
dari tiga narasumber yang merupakan bawahan mereka di PT. Semarang Garment,
yaitu (R4, R5 dan R6). Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan mereka sebagai
berikut:
“Mereka percaya pada yin-yang, dimana karakter manusia ada dua yaitu
baik dan buruk.”
“Saya kurang tahu mengenai pandangan orang Korea mengenai ini. Tapi
yang saya tahu mereka menganut ajaran China yang percaya yin-yang, ada
karakter baik (positif) dan karakter buruk (negatif).”
Berdasarkan pernyataan dari narasumber yang merupakan manajer dari
Korea maupun narasumber karyawan lokal membenarkan pandangan manajer
Korea mengenai karakter dasar manusia tersebut. Hal tersebut membawa pada
kesimpulan bahwa manajer dari Korea pada PT. Semarang Garment memiliki
kecenderungan memandang manusia memiliki karakter dasar baik dan buruk di
dalam dirinya.
2. Relationship among people / focus responsibility (hubungan dengan
individu lain dan fokus tanggungjawab)
Orientasi terhadap tanggung jawab pada orang lain merupakan aspek yang
sangat penting berkaitan dengan hubungan antar manusia dan paling membedakan
antara budaya barat dengan budaya timur. Terdapat tiga jenis orientasi terhadap
orang lain, yaitu individualistik, dimana tujuan individu dianggap mampu
94
mengatasi tujuan kelompok. Selanjutnya collateral atau biasa disebut kolektif,
dimana individu merupakan bagian dari suatu kelompok sosial yang diakibatkan
hubungan yang diperluas secara menyamping. Kemudian yang terakhir adalah
hierarchical, dimana pembagian kekuasaan dan tanggungjawab secara alami
terbagi dalam kelompok berdasarkan hirarki atau kedudukan mereka dalam
sebuah organisasi. Mereka yang berada pada hirarki yang lebih tinggu memiliki
kekuasaan dan tanggungjawab pada mereka yang berada di hirarki lebih rendah.
Berdasarkan hasil olah data wawancara yang diperoleh peneliti, tampak
bahwa manajer dari Korea sangat menganggap tanggung jawab sebagai suatu hal
yang penting dan perlu dilakukan untuk masing-masing pekerjaan individu. Dapat
dilihat pula bahwa mereka juga memperhatikan hirarki atau kedudukan mereka
dalam sebuah struktur organisasi, dimana tanggung jawab juga terbagi
berdasarkan posisi mereka dalam suatu sistem sosial tertent. Hal ini ditunjukkan
dengan jawaban narasumber yang merupakan manajer dari Korea dan diwakili
oleh pernyataan narasumber 1 (R1) sebagai berikut :
“I want make an example in this. You see this watch. The watch has so many
materials that need to work together to make this watch is working. So as an
individual we have to do our best in our each job to get this company work.
This is the responsibility in my opinion. We have to work together in this
company to achieve the main goal of this company.”
“Responsibility. It’s clearly divided as the structure organization.”
Sementara itu, pernyataan dari narasumber yang merupakan karyawan lokal
baik yang berinteraksi langsung dengan manajer dari korea maupun karyawan
yang bekerja operasional di pabrik sebagian besar menyatakan bahwa pembagian
kerja berdasarkan struktur organisasi dan tanggungjawab individu dalam
pekerjaannya masing-masing akan membantu jalannya perusahaan. Pernyataan
tersebut diwakili oleh narasumber 5 (R5), sebagai berikut :
95
“Tanggung jawab dibagi berdasarkan posisi mereka dalam perusahaan dan
setiap orang memegang perannya masing-masing untuk kelangsungan
perusahaan.”
Hal ini lebih dikuatkan lagi dengan penyataan karyawan dari operasional
produksi yang merupakan narasumber 7 (R7) sebagai berikut :
“Tanggung jawab harus dilakukan. Orang Korea cukup tanggungjawab pada
bawahannya.”
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan gaya
Korea mengharapkan kebersamaan dan kerjasama yang baik di dalam pekerjaan untuk
mencapai tujuan perusahaan. Pastinya terdapat hirarki di dalam suatu struktur organisasi,
begitu pula pada PT. Semarang Garment. Mereka melakukan pembagian tanggungjawab
berdasarkan posisi mereka dalam struktur organisasi. Semakin tinggi hirarki mereka
semakin tinggi tanggung jawab yang dipegang karena menyangkut banyak orang di
bawahnya.
3. Relation to broad environment (hubungan dengan alam/lingkungan)
Pada dasarnya, seseorang memiliki cara pandang yang berbeda terkait
hubungannya dengan alam. Hal ini banyak dipengaruhi oleh budaya yang
melatarbelakangi individu tersebut dalam berhubungan dengan alam dan
lingkungan sekitar. Terdapat tiga kategori individu dalam kaitannya dengan sikap
mereka terhadap alam, yaitu mastery, subjugation, dan harmony. Mastery
merupakan sikap manusia yang menguasai, mengendalikan dan mengubah
lingkungan sesuai kebutuhan kita tanpa memperhatikan keselarasan lingkungan.
Sementara subjugation merupakan sikap yang ingin menaklukan lingkungan
namun tidak mengubah elemen-elemen dasar dalam alam. Kemudian yang
terakhir, harmony berarti hidup selaras dengan lingkungan alam maupun
lingkungan sekitar.
96
Berdasarkan hasil olah data wawancara yang diperoleh peneliti, tampak
bahwa manajer dari Korea memilih hidup selaras dan berdampingan dengan alam
juga lingkungan sekitar. Hal ini ditunjukkan dengan tidak banyak yang masalah
yang ditimbulkan dari kegiatan pabrik bagi alam maupun bagi lingkungan sekitar
sehingga semua dapat berjalan selaras tanpa saling merugikan.
Pernyataan yang mendukung tentang pandangan manajer dari Korea yang
berupaya hidup selaras dengan alam dapat disimpulka dari hasil wawancara
dengan narasumber 1, 2 dan 3 (R1, R2 dan R3) yang diwakili dengan pernyataan
dari R1 dan R2 :
“We need to live in harmony with the environment. In my opinion, our
company manage everything quiet well related with the environment and also
the surrounding. It shows that the surrounding do not complain about the
factory activity.”
“Kita harus menjaga lingkungan. Lingkungan harus tetap baik supaya kita
hidup nyaman di dalam lingkungan. Factory kami sudah memiliki manajemen
yang ramah lingkungan.”
Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bawahan mereka yang merupakan
karyawan lokal. Mereka melihat bahwa manajer dari Korea memilih hidup selaras
dengan alam dan lingkungan sekitar mereka. Hal ini didukung oleh pernyataan
dari narasumber 4, 5, 6, 7, dan 8 (R4, R5, R6, R7, R8, R9 dan R10) yang
merupakan karyawan lokal. Berikut diwakili oleh R7 dan R4:
“Hubungan pabrik dengan lingkungan sekitar baik. Banyak pegawai yang
juga berasal dari daerah sekitar sini. Kegiatan pabrik tidak sampai
mengganggu masyarakat. Jam kerjanya juga jam 7 sampai jam 4 sore (sekitar
8 jam).”
“Manajemen pengolahan limbah dan sistem pembuangan di factory ini sudah
cukup baik dan tidak merugikan masyarakat sekitar.”
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manajer dari Korea memiliki
kepemimpinan gaya Korea yang mencoba selaras hidup dengan alam dan lingkungan
97
sekitar. Hal ini sesuai dengan budaya Timur yang kebanyakan diterapkan oleh negara-
negara Asia.
4. Activity (aktivitas)
Orientasi terhadap aktivitas manusia berkaitan dengan sikap manusia
terhadap suatu aktivitas atau kegiatan. Terdapat tiga kategori manusia berdasarkan
cara mereka melakukan aktivitas. Ada masyarakat yang berorientasi pada
pelaksanaan dan melakukan sesuatu (doing), ada pula mpatasyarakat yang
berpikir dan mempertimbangkan setiap keputusan yang akan dilakukan sebelum
melakukan tindakan (thingking) dan yang terakhir tipe masyarakat yang yang
melakukan segala sesuatu secara spontan dan pada waktu yang mereka tentukan
sendiri (being).
Melihat hasil dari olah data wawancara yang dilakukan pada manajer dari
Korea maupun karyawan lokal menunjukkan bahwa orang Korea cukup bijaksana
dalam bertindak, dimana mereka mempertimbangkan setiap keputusan yang akan
mereka ambil dengan cermat namun melakukan tindakan dengan cepat
setelahnya.
Untuk membuktikan hal tersebut, dapat dilihat pada pernyataan narasumber
1, 2 dan 3 (R1, R2 dan R3) yang diwakili oleh R2 dan R3 menyatakan bahwa :
“Kita perlu mempertimbangkan banyak hal dalam bertindak atau melakukan
sesuatu. Tetapi terus menjalankan yang seharusnya kita lakukan.”
“Pekerjaan harus diselesaikan karena merupakan bagian dari tanggung
jawab masing-masing. Think before act but don’t wait too long.”
Hal tersebut dibenarkan oleh bawahan yang berinteraksi langsung dengan manajer
dari Korea, yaitu narasumber 4, 5 dan 6 (R4, R5 dan R6) yang diwakili dengan
pernyataan dari R4 sebagai berikut :
“Saya melihat atasan saya (manajer) berusaha melakukan segala sesuatunya
dengan hati-hati (penuh pemikiran) tetapi mereka cepat dalam bertindak.”
98
Kesimpulan yang dapat ditarik dari karakter gaya kepemimpinan korea terkait
dengan cara mereka melakukan tindakan yaitu thingking, dimana mereka
mempertimbangkan setiap hal yang akan dilakukan tetapi memilih bertindak dengan
cepat.
5. Time (waktu)
Pada dimensi time atau waktu ini akan dianalisis bagaimana manajer dari
Korea menghargai sebuah waktu dan orientasi mereka terhadap masa lalu, saat ini
atau pun masa depan.
Berikut adalah pernyataan manajer dari Korea tentang waktu, yang diwakili
oleh narasumber 1 (R1) dan narasumber 3 (R3):
“Of course we believe our past and want to keep our tradition until now. But
the young generations now get a lot influenced by western culture. Korea have
5000 years history. Also history of each family is important for us.”
“Past made what we are now. The present (now) made what we are in the
future. I will keep my tradition from the past (of my country) to work in
everywhere even it’s abroad.”
“Jam kerja di Korea lebih panjang daripada orang Indonesia. Kebiasaan
kami bekerja dengan cepat dengan hasil yang baik.”
Melihat pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang Korea sangat
menghargai sejarah dan tradisi dari negaranya. Jika memungkinkan akan terus dijaga dan
dilestarikan, tetapi tidak berarti setiap hal harus dilakukan berdasarkan tradisi dan adat-
istiadat setempat. Terlebih lagi bagi orang Korea yang hidup di luar negaranya, mereka
berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan budaya di negara dimana
mereka tinggal.
Hal ini didukung oleh pernyataan karyawan yang berinteraksi langsung dengan
manajer dari Korea dan diwakili dengan pernyataan dari narasumber 5 (R5) dan
narasumber 6 (R6) sebagai berikut:
“Perbedaan budaya, ras maupun gender dijembatani dengan peraturan kerja
bersama yang ada sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Mereka
berusahan menyesuaikan budaya kita.”
99
“Mereka (manajer) sangat menghargai waktu. Loyalitas orang Korea pada
pekerjaan sangat tinggi. Pernah ada kejadian dimana seorang manajer
sedang sakit, harus infus 2 jam istirahat di mess tetapi yang mengejutkan
setelah itu dia tetap kembali bekerja di factory.”
“Mereka (manajer) juga pernah bercerita pada saya, di pabrik-pabrik di
Korea jika sesorang wanita harus melahirkan bahkan tetap bekerja sampai
tiba saatnya dia melahirkan kemudian dibawa ke rumah sakit, tetapi 3 jam
setelah persalinan mereka siap kembali bekerja. Hal seperti ini terjadi di
Korea.”
Menyimpulkan pernyataan dari manajer Korea dan bawahan mereka yang
merupakan karyawan lokal, diketahui bahwa gaya kepemimpinan Korea memiliki
dedikasi pada pekerjaan yang sangat tinggi, menghargai waktu dan berusaha menjaga
tradisi mereka sekalipun harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana dia tinggal
dan bekerja untuk hal-hal tertentu yang dianggap perlu.
6. Space (ruang)
Dimensi space atau keruangan ini membedakan pandangan orang terhadap
sebuah ruang, khususnya tempat bekerja di PT. Semarang Garment dan
bagaimana mereka menginginkan tempat tersebut agar tetap terjaga secara pribadi
(private) atau bisa berbagi dengan orang lain (public).
Beberapa diantara mereka menggunakan ruang tersendiri sebagai ruang
kerja namun ada beberapa manajer yang memiliki ruang kerja tanpa sekat dan
menyatu dengan karyawan lain yang merupakan bawahan dalam depertemen yang
sama. Hal tersebut ditunjukkan dengan pernyataan dari manajer Korea maupun
karyawan lokal yang diwakili oleh Narasumber 2 dan 4 (R2 dan R4) berikut :
“Saya suka ruang yang privat. Tetapi ruangan saya di sini sudah cukup buat
saya. Saya menyatu dengan pekerja yang lain.”- R2
“Terdapat ruang-ruang tertentu yang khusus bagi atasan dan tidak dapat
dimasuki oleh karyawan tanpa ijin terlebih dahulu kepada manajer.”- R4
Pernyataan perwakilan dari pihak manajer dan karyawan lokal tersebut
menunjukkan kriteria orang Korea dalam menentukan ruangannya.
100
4.2.4.2. Dimensi Budaya Pola-pola Parson
Selain menggunakan enam dimensi Kluchkhon dan Strotdbeck untuk
mengamati dan menganalisis kepemimpinan gaya Korea di Indonesia, juga
didukung oleh lima dimensi dari pola-pola Parson. Berikut akan diberikan
pembahasan secara lengkap.
1. Afektivitas – netralitas
Dimensi ini menentukan bagaimana pandangan orang terhadap sebuah
organisasi dimana kita menjadi bagian dari organisasi tersebut, apakah sebaiknya
menciptakan kenyamanan dan kepuasan emosional diantara anggota organisasi
atau sebaiknya bersikap netral dan tidak terlalu terikat dengan seluruh organisasi
tersebut.
Berdasarkan olah data hasil wawancara dengan narasumber yang
merupakan manajer dari Korea dan bawahan yang merupakan karyawan lokal
memiliki pernyataan jawaban yang hampir serupa. Hal ini ditunjukkan dengan
perwakilan pernyataan dari narasumber 1 (R1) dan narasumber (R4) sebagai
berikut :
“So far i’m satisfied with the people here. Only the first two years i felt stress
and alot of headache, but now i think we can work together profesionally.
I’m trying to act the same for all the employees. I don’t personally getting
close with one of them or some of them. I think i have to be fair to all the
employees.”- R1
Para manajer bersikap serius saat bekerja dan sangat menjaga jarak antara
atasan dengan bawahan.- R4
Menyimpulkan kedua pendapat tersebut yang berasal dari narasumber yang
memimpin (manajer dari Korea) dan bawahan (karyawan lokal) diketahui bahwa
kepemimpinan gaya Korea yang mereka terapkan di Semarang Garment memilih
101
hubungan yang lebih netral antara atasan dengan bawahan dan tidak terlalu
menjalin hubungan personal selain hubungan kerja.
2. Orientasi diri – orientasi kolektif
Orientasi diri mementingkan kepentingan individu. Sementara orientasi
kolektif mementingkan kepentingan kelompok dan orang lain yang menjadi
bagian kelompok tersebut.
Berdasarkan olah data hasil wawancara dengan narasumber yang
merupakan manajer dari Korea dan bawahan yang merupakan karyawan lokal
memiliki pernyataan jawaban yang hampir serupa. Hal ini ditunjukkan dengan
perwakilan pernyataan dari narasumber 1 (R3) dan narasumber (R6) sebagai
berikut :
“Kerja bersama penting untuk mencapai tujuan company. Masing-masing
orang punya pekerjaan yang harus selesai dengan baik untuk dapat membuat
factory ini berjalan baik.” – R3
“Kerjasama dan kerjakeras sangat ditekankan di company kami.” – R6
Menyimpulkan dari dua pernyataan dari kedua pihak tersebut, menunjukkan
bahwa orientasi kolektif merupakan salah satu kriteria kepemimpinan gaya Korea
yang diterapkan di PT. Semarang Garment.
3. Universalisme – partikularisme
Dimensi ini menentukan bagaimana seseorang melihat sesuatu. Ada yang
melihat sesuatu secara keseluruhan dan garis besarnya saja, sementara yang lain
melihat sesuatu secara spesifik. Dalam kaitannya dengan hubungan kerja di PT.
Semarang Garment, dimensi ini akan membantu dalam menganalisis bagaimana
gaya kepemimpinan Korea melihat dan memaknai hubungan dengan bawahan.
Apakah terjadi secara spesifik melebur dengan suku, agama dan kelompok
102
tertentu atau hubungan yang terjadi hanya mencakup standar-standar yang juga
diterapkan pada semua orang lain dan tidak terlalu mendalam.
Berdasarkan olah data hasil wawancara dengan narasumber yang
merupakan manajer dari Korea dan bawahan yang merupakan karyawan lokal
memiliki pernyataan jawaban yang saling mendukung dan menguatkan
pernyataan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan perwakilan pernyataan dari
narasumber 1 (R2) dan narasumber 6 (R6) sebagai berikut :
“Pembagian tanggung jawab sesuai struktur organisasi dan job masing-
masing pegawai.” – R2
“Saya bersikap netral pada seluruh karyawan dan berusaha berlaku sama
untuk semuanya.” – R6
“Keterlibatan antara manajer dengan bawahannya terjadi sebatas hubungan
kerja. Tetap ada jarak antara atasan dengan bawahan.” – R6
Menurut pernyataan kedua pihak, baik manajer dari maupun karyawan
lokal menekankan bahwa hubungan yang terjadi antara atasan dengan bawahan
hanya sebatas rekan kerja dan hubungan profesional yang dibatasi oleh aturan-
aturan umum selayaknya pada sebuah perusahaan dan saling menghormati
berdasarkan kedudukan di dalam struktur organisasi perusahaan, tidak ada
keterlibatan secara khusus yang melebihi hubungan kerja.
4. Askripsi – prestasi
Penilaian seorang individu didasarkan pada askripsi atau prestasi yang dia
peroleh. Dimensi akripsi-prestasi ini membantu peneliti dalam menganalisis
mengenai karakter kepemimpinan gaya Korea, apakah mereka memiliki
kecenderungan menilai orang lain berdasarkan klasifikasinya dalam masyarakat
atau sebuah prestasi yang dia peroleh sekalipun dia bukan dari kelas sosial yang
terpandang.
103
Berdasarkan olah data hasil wawancara dengan narasumber yang
merupakan manajer dari Korea dan bawahan yang merupakan karyawan lokal
memiliki pernyataan jawaban yang saling mendukung dan menguatkan
pernyataan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan perwakilan pernyataan dari
narasumber 1 (R1) dan narasumber 6 (R6) sebagai berikut :
“Different class of society does exist. Every person has a history and has a
tree of family. It’s very wide cases. I can’t say it in a word. Long time ago, we
have something like that. Kim family, Choi family, etc is famous as the rich
family. It was very common. Some name seen as rich families, some name seen
as lower social class by the society. But nowadays, they are judged by the
achievement they got. We have to see the people from the higher class so that
we able to try harder and work harder for someday to be one of them. I think
class of society in every part of the world does exist, even in America or in
Indonesia.”
“Saya pernah mendengar dari atasan saya bahwa terdapat klasifikasi sosial
di Korea. Nama “Kim” adalah nama yang dikenal keluarga kaya begitu pula
nama-nama lain dengan kelas sosial yang berbeda. Pemilik perusahaan
Semarang Garment ini bukan berasal dari keluarga dengan nama dan latar
belakang yang terpandang. “Byun” adalah nama dari kelas sosial yang cukup
bawah namun kerja kerasnya sejak muda membuahkan hasil hingga dia
menjadi orang yang terpandang saat ini.”
Berdasarkan justifikasi di atas, dapat dikatakan bahwa karakter manajer dari
Korea menyatakan masih melihat seseorang berdasarkan kedudukannya di dalam
kelas sosial. Hal ini lazim di Korea Selatan. Nama keluarga tertentu dengan
sejarah keluarganya dipandang sebagai keluarga kaya dan memiliki pengaruh di
Korea. Ada pula nama-nama lain dengan kelas sosial tertentu. Namun, seiring
berjalannya waktu dan perkembangan zaman dapat dikatakan bahwa pandangan
askriptif dari orang Korea mulai bergeser ke pandangan dengan orientasi prestasi
ketika melihat orang lain. Tidak dipungkiri jika nama sebuah keluarga masih
dipandang dan memiliki nilai tersendiri bagi mereka, tetapi pencapaian seseorang
hingga kini menjadi sukses juga menjadikan orang tersebut terpandang di Korea
Selatan.
104
5. Spesifitas – kekaburan
Hubungan dengan bawahan yang diterapkan oleh manajer dari Korea pada
PT. Semarang Garment dilakukan dengan keterlibatan yang cukup dekat dimana
kewajiban timbal-balik itu terbatas dan dibatasi dengan tepat (spesifik) atau
kepuasan yang diterima dan diberikan oleh pihak yang saling berhubungan sangat
luas sifatnya (kabur) tidak menentu.
Berdasarkan olah data hasil wawancara dengan narasumber yang
merupakan manajer dari Korea dan bawahan yang merupakan karyawan lokal
memiliki pernyataan jawaban yang saling mendukung dan menguatkan
pernyataan tersebut. Analisis untuk menentukan kriteria gaya kepemimpinan
Korea bersifat spesifik atau terdapat kekaburan hampir serupa dengan analisis
pada dimensi universalisme dan partikularisme. Hal ini ditunjukkan dengan
perwakilan pernyataan dari narasumber 1 (R2) dan narasumber 6 (R6) sebagai
berikut :
“Pembagian tanggung jawab sesuai struktur organisasi dan job masing-
masing pegawai.” – R2
“Saya bersikap netral pada seluruh karyawan dan berusaha berlaku sama
untuk semuanya.” – R6
“Keterlibatan antara manajer dengan bawahannya terjadi sebatas hubungan
kerja. Tetap ada jarak antara atasan dengan bawahan.” – R6
Menurut pernyataan kedua pihak, baik manajer dari Korea menekankan
bahwa hubungan yang terjadi antara atasan dengan bawahan hanya sebatas rekan
kerja dan hubungan profesional yang dibatasi oleh aturan-aturan umum
selayaknya pada sebuah perusahaan dan saling menghormati berdasarkan
kedudukan di dalam struktur organisasi perusahaan, tidak ada keterlibatan secara
khusus yang melebihi hubungan kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
105
hubungan timbal-balik yang terjadi adalah kewajiban yang terbatas dan dibatasi
dengan tepat sehingga hubungan yang demikian disebut spesifik dan sebatas
profesionalisme dalam pekerjaan.
Berikut adalah tabel yang merangkum keseluruhan hasil analisis yang
membahas mengenai kepemimpinan gaya Korea yang diterapkan di Indonesia
berdasarkan setiap dimensi yang telah dibahas sebelumnya.
Tabel 4.2
Hasil Analisis Mengenai Kepemimpinan Gaya Korea Berdasarkan Dimensi
Budaya Kluchkhon & Strodtbeck dan Pola-pola Parson
No Dimensi Kepemimpinan gaya
Korea yang diterapkan
Justifikasi
1. Karakter dasar
manusia
Percaya bahwa manusia
memiliki dua karakter :
baik dan buruk
R1, R2 dan R3 menyatakan
bahwa manajer dari Korea
meyakini dua macam karakter
: baik dam buruk di dalam diri
manusia (mengenai karakter
dasar manusia) dan dibenarkan
atau divalidasi oleh pernyataan
oleh R4, R5 dan R6.
2. Fokus
tanggungjawab
Tanggung jawab bersama
Kolektif/ berkelompok
Pernyataan R1, R2 dan R3
mengarah pada karakter
manajer Korea yang fokus
pada tanggung jawab kolektif
dan divalidasi oleh pernyataan
R4, R5, R6, R7 dan R8.
3. Hubungan dengan
lingkungan
harmony : hidup selaras
dengan alam
Pernyataan R1, R2 dan R3
mengarah pada karakter
manajer Korea dalam
hubungan dengan lingkungan
yang harmony dan divalidasi
oleh pernyataan R4 sampai
dengan R10 mengenai hal
tersebut.
4. Aktivitas Thinking :
mempertimbangkan setiap
aspek dalam mengambil
keputusan.
Pernyataan R1, R2 dan R3
mengarah pada karakter
aktivitas thinking dan
divalidasi oleh pernyataan R4,
R5dan R6.
5. Waktu Sangat menghargai Pernyataan R1, R2 dan R3
mengarah pada dimensi waktu
106
waktu
Tradisi dan sejarah
dipegang erat
yang menunjukkan karakter
manajer Korea sangat
memperhatikan past serta
menghargai setiap waktu yang
dimiliki. Tetapi juga
memikirkan masa depan, tidak
terpaku pada masa lalu. Hal ini
divalidasi oleh pernyataan R4
sampai dengan R9.
6. Ruang Lebih memilih ruang untuk
pribadi.
Pernyataan R1, R2 dan R3
mengarah pada dimensi ruang
yang menunjukkan manajer
Korea lebih memilih private
namun penyesuain dengan
kondisi yang ada telah
dilakukan. Hal ini divalidasi
oleh pernyataan R4 s.d. R6.
7. Afektivitas –
netralitas afektif
Netralitas afektif Pernyataan R1, R2 dan R3
mengarah pada dimensi
netralitas dimana
menunjukkan pandangan
manajer Korea yang afektif
dan hal ini telah divalidasi oleh
pernyataan R4 s.d. R10
8. Orientasi diri –
orientasi kolektif
Orientasi kolektif Pernyataan R1, R2 dan R3
menunjukkan bahwa manajer
Korea memiliki orientasi
kolektif. Hal ini divalidasi oleh
pernyataan R4 s.d. R6.
9. Universalisme –
partikularisme
Universalisme Pernyataan R1, R2 dan R3
menunjukkan bahwa manajer
Korea memiliki pandangan
universalisme dan telah
divalidasi oleh pernyataan R4
s.d. R6.
10. Askripsi – prestasi Askripsi yang mulai
bergeser pada prestasi
Pernyataan R1, R2 dan R3
menunjukkan bahwa manajer
Korea memiliki pandangan
askripsi namun mulai bergeser
pada prestasi. Hal ini telah
divalidasi oleh pernyataan R4
s.d. R6.
11. Spesifitas –
kekaburan
Spesifik. Pernyataan R1, R2 dan R3
menunjukkan bahwa manajer
Korea memiliki pandangan
spesifik dan telah divalidasi
oleh pernyataan R4 s.d. R6.
Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2013
107
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
PT. Semarang Garment merupakan perluasan usaha dari perusahaan
internasional Kukdong Corporation yang berpusat di Seoul, Korea Selatan.
Perusahaan yang dipimpin langsung oleh seorang pimpinan yang juga sebagai
pemilik perusahaan yaitu Byun Hyo Su, berkebangsaan Korea Selatan ini telah
mengembangkan usahanya ke beberapa negara di dunia. Pada PT. Semarang
Garment terdapat 1451 karyawan pada factory I dan sejumlah 1121 karyawan
pada factory II sehingga total karyawan keseluruhan adalah 2572 orang yang
merupakan penduduk lokal.
Perusahaan ini memiliki pimpinan (presiden utama) dan jajaran manajer
yang merupakan orang Korea Selatan dan telah bekerja serta tinggal di sini sesuai
dengan penugasan yang mereka peroleh dari kantor pusat di Kukdong
Corporation, Seoul. Perbedaan budaya terjadi pada perusahaan ini, dimana
kepemimpinan di perusahaan tersebut memiliki latar belakang budaya Korea
sementara pengikut mereka adalah karyawan yang merupakan penduduk lokal
dengan latar belakang kebudayaan Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Proses
kepemimpinan lintas budaya dari karakter kepemimpinan gaya Korea yang
disesuaikan dengan pengikut yang berkebudayaan lokal merupakan suatu
fenomena yang unik dan bagaimana mereka dapat melakukan kerja sama dengan
baik di tengah perbedaan yang ada merupakan sesuatu yang menarik.
108
Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya diketahui karakter gaya
kepemimpinan Korea yang diterapkan pada PT. Semarang Garment sesuai dengan
dimensi yang membatasi penelitian ini, yaitu dimensi budaya dari Kluchkhon dan
Strodtbeck serta pola-pola budaya Parson. Pada umumnya budaya Korea Selatan
merupakan bagian dari budaya Timur sehingga karakter gaya kepemimpinan yang
diterapkan tidak sulit untuk diikuti bagi karyawan lokal pada perusahaan tersebut.
5.2 Implikasi Kebijakan
1. Hasil penelitian ini menunjukkan mengenai karakter kepemimpinan gaya
Korea di Indonesia khususnya pada PT. Semarang Garment. Hal ini
bermanfaat bagi perusahaan jika mereka dapat mengelola perbedaan budaya
lokal dengan gaya kepemimpinan Korea dimana perusahaan tersebut
memiliki jajaran manajer dan pimpinan dari Korea, khususnya Korea Selatan
dan karyawan lokal yang kebanyakan merupakan penduduk Jawa Tengah.
2. Hasil analisis mengenai dimensi karakter dasar manusia menunjukkan bahwa
budaya Korea cenderung melihat manusia memiliki dua macam karakter di
dalam dirinya, baik dan buruk. Hal ini menentukan gaya atau karakter mereka
dalam berhubungan dengan orang lain. Tentunya mereka akan berhati-hati
dalam berhubungan dengan orang lain. Manajer dari Korea akan terlebih
dahulu membaca keadaan jika berkomunikasi dengan karyawan lokal dan
berusaha menguatkan sisi baik dari karyawan lokal dan membuat karyawan
lokal meninggalkan sisi buruknya dengan pelatihan yang diberikan dalam
perusahaan. Sebagian besar dari manajer Korea mempercayai bahwa
lingkungan yang baik dapat membawa seseorang tumbuh menjadi lebih baik.
109
Berdasarkan fakta tersebut, mereka akan mengupayakan lingkungan yang
baik, rajin, disiplin dan kerja keras dalam perusahaan agar diikuti oleh
karyawan lokal.
3. Hasil analisis mengenai fokus tanggung jawab membuktikan bahwa manajer
dari Korea menerapkan kepemimpinan dengan karakter yang mementingkan
tanggung jawab terhadap orang lain, yaitu tanggung jawab bersama dalam
kelompok. Hal ini berkaitan dengan kerja mereka yang memperhatikan
kualitas kerja sama dan kerja keras antar karyawan untuk memenuhi dan
mewujudkan target perusahaan.
4. Hasil analisis mengenai dimensi aktivitas menunjukkan bahwa dalam
melakukan tindakan, para manajer Korea cenderung mempertimbangkan
berbagai aspek yang terkait dengan tindakan tersebut. Kecenderungan untuk
berpikir dahulu (thinking) sebelum bertindak merupakan salah satu karakter
dari manajer Korea, namun hal ini tidak menjadikan mereka lamban dalam
bertindak. Segala pertimbangan dilakukan dengan baik dan tindakan cepat
dilaksanakan. Hal seperti ini juga sangat baik bagi perusahaan.
5. Hasil analisis mengenai hubungan dengan lingkungan menunjukkan bahwa
karakter manajer Korea memiliki pandangan yang sama dengan budaya
Timur pada umumnya yaitu senantiasa berkeinginan hidup selaras dengan
alam maupun lingkungan (harmony). Hal ini membantu dan memudahkan
interaksi perusahaan dengan lingkungan sekitar karena dengan manajemen
yang baik terhadap lingkungan akan meminimalkan konflik dengan
lingkungan masyarakat sekitar dan tidak mengganggu alam. Karakter seperti
110
ini merupakan hal yang positif bagi perusahaan maupun lingkungan di sekitar
perusahaan.
6. Hasil analisis mengenai dimensi waktu menunjukkan bahwa karakteristik
kepemimpinan gaya Korea memiliki apresiasi yang sangat tinggi terhadap
waktu dimana mereka memanfaatkan setiap waktu dengan baik, khususnya
untuk bekerja sesuai dengan prinsip mereka kerja keras untuk sesuatu yang
lebih baik. Selain itu, mereka juga berpegang pada masa lalu (past) sehingga
masih memegang tradisi dan kebudayaan dari negaranya yang memiliki
budaya Timur dan adat istiadat tersendiri. Hal ini tidak menjadikan mereka
terbelenggu dalam masa lalu, namun tradisi baik yang dipegang oleh
masyarakat Korea membawa mereka pada perilaku yang baik sesuai adat
ketimuran tetapi perencanaan terhadap masa depan juga sangat
dipertimbangkan dengan matang. Berdasarkan kriteria yang demikian,
pengaruh yang diberikan manajer dari Korea akan terasa postif bagi
lingkungan perusahaan dan memudahkan kerja sama dengan karyawan lokal.
7. Mengenai dimensi keruangan atau space, hasil analisis pada bab sebelumnya
menunjukkan bahwa karakter manajer Korea menginginkan sebuah ruang
yang terjaga secara privat untuk dirinya sendiri dan tidak terganggu dengan
karyawan lain. Keadaan pada PT. Semarang Garment menunjukkan bahwa
beberapa ruang manajer menyatu dengan karyawan lain tanpa diberi sekat
tersendiri menjadikan mereka mengubah pandangan mengenai ruang yang
bersifat pribadi dan menyesuaikan dengan keadaan dan lingkungan
perusahaan.
111
8. Terkait dengan afektivitas dan netralitas afektif, sesuai dengan hasil analisis,
menunjukkan bahwa karakter manajer Korea yang bersikap netralitas afektif
dimana terlihat secara jelas bagi karyawan jika mereka cukup membatasi diri
dengan karyawan khususnya di lingkungan kerja dan bersikap netral terhadap
seluruh karyawan. Sisi baik dari karakter yang demikian adalah terciptanya
netralitas dalam penilaian atasan terhadap bawahan karena tidak ada tendensi
tertentu terhadap kelompok tertentu di dalam perusahaan yang dianggap
memiliki hubungan lebih baik atau bahkan hubungan yang kurang baik
dengan atasan.
9. Karakter yang lain dari manajer dari Korea berdasarkan hasil analisis yang
telah dilakukan sebelumnya adalah kecenderungan mereka berorientasi pada
kelompok dan kerja sama tim sangat dipentingkan dalam perusahaan.
10. Terdapat pula kriteria yang menunjukkan pandangan universalisme yang
menjadi salah satu karakter manajer Korea di perusahaan Semarang Garment.
Hal ini hampir serupa dengan netralitas yang dilakukan oleh manajer terhadap
bawahan, tidak ada hubungan yang lebih dari hubungan profesional kerja bagi
atasan yang merupakan manajer dari Korea dengan karyawan lokal.
11. Askripsi merupakan suatu pandangan oleh masyarakat tertentu yang melihat
orang lain berdasarkan struktur tertentu di dalam sebuah lingkungan atau
berdasarkan sejarahnya di dalam masyarakat. Hal ini diakui oleh manajer dari
Korea bahwa pandangan tersebut memang ada di Korea, dimana sebuah nama
dengan marga tertentu memiliki pengaruh lebih dalam masyarakat dan sangat
dihargai, ada pula nama dengan marga tertentu yang dianggap kelas lebih
rendah dalam masyarakat. Perkembangan zaman membawa perubahan
112
mengenai pandangan tersebut. Pergeseran pandangan itu ditunjukkan dengan
pandangan terhadap seseorang yang mulai mempertimbangkan prestasi dalam
menilai orang lain sekalipun dari kelas sosial yang bagi mereka dari tingkatan
cukup rendah dalam masyarakat akan dipandang baik jika mereka memiliki
pencapaian tertentu dan dilihat oleh masyarakat lain.
12. Spesifik menunjukkan hubungan yang tercipta antara manajer dari Korea
dengan karyawan lokal sangat memperhatikan batasan tatanan dan aturan
yang telah ada dan disepakati bersama. Hubungan yang demikian dapat
dikatakan spesifik dan sebatas profesional kerja.
5.3 Keterbatasan Penelitian
1. Penelitian hanya mengambil objek penelitian pada satu perusahaan multi
nasional dari Korea di Indonesia.
2. Penelitian ini hanya dibatasi oleh dimensi budaya dari Kluchkhon &
Strodtbeck serta pola-pola budaya Parson. Untuk melihat kepemimpinan gaya
Korea dapat didukung dengan teori budaya nasional lain yang mendukung
kedalaman penelitian.
5.4 Agenda Penelitian Mendatang
1. Agenda penelitian mendatang diharapkan dapat meneliti mengenai
kepemimpinan gaya Korea pada beberapa perusahaan multi nasional dari
Korea di Indonesia untuk melengkapi justifikasi mengenai karakteristik
budaya dan gaya kepemimpinan dari Korea.
113
2. Dalam penelitian selanjutnya dapat pula digunakan teori budaya nasional
yang lain, seperti teori Bass dan Avolio maupu teori Hofstede yang
mendukung dalam penelitian mengenai kepemimpinan gaya Korea atau
karakteristik kepemimpinan negara lain di Indonesia.
3. Pengembangan penelitian juga dapat dilakukan mengenai kepemimpinan
lintas budaya dari negara selain Korea pada perusahaan multi nasional
tertentu yang lain di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Ajiferuke, M. And Boddewyn JJ, 1970, “Culture and Other Explanatory
Variables in Comparative Management Studies”, Academy of Management
Journal, Vol. 13, pp.153-163.
Aziati, Fadillah. 2011. Analisis Pengaruh Budaya Nasional, Kompetensi
Komunikasi Lintas Budaya, dan Budaya Organiasasi Terhadap Kompetensi
Negosiaasi Berbasis PSA (Problem Solving Approach). Universitas
Diponegoro. Semarang.
Ball, Donald A. et al., 2004, International Business, The Challenge of Global
Competition, Ninth Edition, McGraw-Hill Companies, Inc, New York.
Chang, Lieuh-Chiung, 2002, “Cross Cultural Differences in International
Management Using Kluckholn-Strodtbeck Framework”, Journal of
American Academy of Business, Cambridge, September 2002, Vol.2, No.1
Czinkota, Ronkainen and Moffet. 1994, International Business, Third Edition,
The Dryden Press.
Fukushige, A and David P Spicer, 2006, “Leadership Preferences in Japan: an
Exploratory Study”, Leadership and Organizational Development Journal,
Vol.28, No.6, pp 508-530
Hofstede, G. 1984, Culture’s Consequences: International Differences in Woek-
related Values. Sage Publication. Beverly Hills.
Hubbard, A. 2003. Accommodating diversity in training environment. Mortgage
Banking, 63 (4106).
Jauhari, Hadziq. 2010. Filosofi Tri Dharma Pada Kepemimpinan Budi Santoso di
Suara Merdeka. Universitas Diponegoro, Semarang.
Keunshin, Yoo, 1999, “The Traits and Leadership Styles of CEO’s in Korean
Companies”, International Studies of Management & Organization, Vol.28,
No.4 pg.40
Kim, Myung-Oak dan San Jaffe. 2010. The New Korea, Mengungkap
Kebangkitan Ekonomi Korea Selatan. Kompas Gramedia. Jakarta.
Koentjaraningrat. 1995. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta :
Djambatan.
Kotler, J.P. & Heskett, J.L. 1992. Corporate culture & performance. New York:
Free Press.
Kusuma, Dewantya. 2011. Analisis Penerapan Filosofi Semar Sang Pamomong
Pada Era Kepemimpinan Kukrit Suryo Wicaksono di Suara Merdeka.
Universitas Diponegoro, Semarang.
Kumalaningrum, M.P. 1999. Multicultural organization; Strategi mengelola
keberagaman tenaga kerja. Usahawan, No. 2 Th. XXVII.
Littrel, Romie F, 2005, “Preferred Leadership Behaviours: Exploratory Results
from Romania, Germany, and the UK”, Journal of Management
Development, Vol. 24, No.5, pp. 421-442
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja
Rosdakarya. Bandung.
Nursanti, T.D. 2000. Strategi pengelolaan menuju organisasi multiculture.
Usahawan, No. 11 Th. XXIX
Mas’ud, Fuad. 2004. Survai Diagnosis Organisasional Konsep & Aplikasi.
UNDIP. Semarang.
Pan, Yue and friends, 2010, “A Cross-cultural Investigation of Work Values
among Young Excecutives in China and the USA, Cross Cultural
Management: An Internasional Journal, Vo.17, No.3, pp. 283-298
Pihatin Lumbanraja, 2008. Tantangan Bagi Kepemimpinan Lintas Budaya,
Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
Rachel K. 2004. Culture, intercultural communication competence, and sales
negotiation: a qualitative research approach.
Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008. Perilaku Organisasi. Salemba
Empat, Jakarta.
Seng, Ann Wang. 2013. Rahasia Bisnis Orang Korea. Jakarta : Noura Books.
Sugiarto, 2007. Pengaruh Kepemimpinan, Disiplin, dan Budaya Kerja Terhadap
Kepuasan Kerja Karyawan PT. Primatexco Indonesia. Universitas
Diponegoro. Semarang.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
Suutari, Vesa and friends, 2002, “The Challenge of Cross-cultural Leadership
Interaction: Finnish Expatriates in Indonesia, Career Development
International, Vol.7, No.7, pp 415-429
Trompenaars, F., 1994, Riding the Waves of Culture. Understanding Cultural
Diversity in Business, The Economist Books, London.
Weinshall. 1993, Societal Culture and Management, New York: Walter de
Gruyter.
Yuki, G.A. 1994, Leadership in Organization. Prentice-Hall. Englewood Cliffs,
NJ.