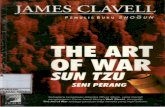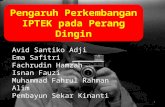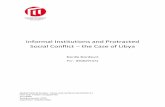Penyebab dan Permulaan Perang Sipil di Sri Lanka (1983-2009) berdasarkan Teori Protracted Social...
Transcript of Penyebab dan Permulaan Perang Sipil di Sri Lanka (1983-2009) berdasarkan Teori Protracted Social...
Penyebab dan Permulaan Perang Sipil di
Sri Lanka (1983-2009)Disusun untuk Memenuhi Tugas Makalah Akhir Mata Kuliah
Perdamaian dan Resolusi Konflik
Disusun oleh:
Tiara Maharanie (1206210856)
Program Studi S1 Reguler Ilmu Hubungan Internasional
Semester Genap 2013/2014
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA
2014BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perang Sipil Sri Lanka merupakan konflik berkepanjangan yang
berlangsung selama lebih dari 25 tahun, tepatnya sepanjang periode
1983 hingga 2009. Konflik terbuka saat kelompok militan Liberation
Tigers of Tamil Eelam (LTTE) melalukan pemberontakan terhadap
pemerintah sebagai upaya mendirikan negara Tamil merdeka yang
disebut Tamil Eelam di wilayah Utara dan Timur Sri Lanka. Seperti
namanya, LTTE merupakan organisasi militan yang dibentuk oleh
etnis Tamil sebagai etnis minoritas yang beragama Hindu, terhadap
pemerintah yang mayoritas dipegang oleh etnis terbesar yaitu
Sinhala dan mayoritas beragama Budha.
Akar permasalahan konflik Sri Lanka berawal dari masa
pendudukan kolonial Inggris, ketika Sri Lanka masih bernama
Ceylon. Perbedaan posisi antara Sinhala dan Tamil pada masa
kolonial memberikan ketegangan bagi hubungan sosial dan politik
antar keduanya. Pasca Ceylon merdeka pada 1948, Parlemen Ceylon
mengeluarkan regulasi yang disebut sebagai Akta Kewarganegaraan
Ceylon yang memberikan bentuk diskriminasi bagi minoritas Tamil
dengan membuat mereka hampir tidak mungkin mendapatkan hak
warganegara. Sekitar lebih dari 700.000 warga Tamil dibuat stateless.
1
Selama tiga dekade berikutnya, lebih dari 300.000 warga Tamil
dideportasi kembali ke India. Kemudian, pada 1956 Perdana Menteri
S. W. R. D. Bandaranaike menetapkan bahasa Sinhala sebagai bahasa
nasional menggantikan bahasa Inggris. Hal ini dianggap sebagai
bentuk diskriminasi lain bagi Tamil untuk mencegah Tamil Sri Lanka
bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan layanan publik lainnya.
Tidak hanya itu, beragam bentuk diskriminasi lain terhadap
Tamil muncul dan semakin meningkat. Hal ini menjadi faktor
eskalasi gerakan separatis, yang puncaknya terjadi pada 1983
ketika LTTE melakukan penyerangan yang menewaskan 13 tentara Sri
Lanka. Peristiwa tersebut menimbulkan kericuhan anti-Tamil di
ibukota Kolombo. Ratusan warga meninggal, ribuan melarikan diri,
dan hal ini menjadi awal konflik yang disebut sebagai “Perang
Eelam Pertama”.
Selama lebih dari 25 tahun, konflik berkempanjangan terjadi,
bahkan terdapat empat fase konflik hingga mencapai “Perang Eelam
Keempat”. Konflik ini tentu mempengaruhi kondisi internal Sri
Lanka, baik terhadap masyarakat, lingkungan, ekonomi, dan politik
domestik maupun internasional. Disinyalir, konflik berkepanjangan
tersebut telah menghabiskan biaya sebesar 1.443 rupee Sri Lanka,
termasuk untuk peningkatan anggaran militer, biaya kerusakan dan
rekonstruksi, serta hilangnya output ekonomi dan pariwisata. Sejak
1983, diperkirakan sebanyak 70.000 warga meninggal akibat konflik—
mayoritas adalah warga etnis Tamil, Sinhala, dan Muslim.
1.2 Perumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut, muncul pertanyaan “Bagaimana
gambaran secara umum dan penyebab perang sipil di Sri Lanka?”.
Maka, dalam tulisan ini yang menjadi fokus adalah apa saja
penyebab konflik terjadi, mulai dari keterlibatan aktor, interest,
2
dan bagaimana proses pecahnya konflik. Dengan berangkat dari
ketiga hal tersebut, makalah ini akan menganalisis mengenai bentuk
awal konflik di Sri Lanka yang berlangsung selama periode 1983 –
2009.
1.3 Kerangka Teori
1.3.1 Teori Protracted Social Conflict
Pada pertengahan 1990-an, fokus analisis kajian perang dan
perdamaian mulai banyak dikaitkan dengan istilah internal conflicts, new
wars, small wars, civil wars, ethnic conflict, humanitarian, dan sebagainya.
Menurut Holsti dikutip oleh Ramsbotham, status dan peran
masyarakat dalam suatu negara serta nature dari weak state merupakan
gambaran perang saat ini dan masa depan, dimana hal ini berbeda
dengan pemahaman tradisional yang fokus pada kajian perang dan
perdamaian yang bersifat inter-state. Berkaitan dengan hal ini, Edward
Azar dengan teori protracted social conflict (PSC), memahami konflik
sebagai, “the prolonged and often violent struggle by communal groups for such basic
needs as security, recognition and acceptance, fair access to political institutions and
economic participation”.1 Dalam hal ini, Azar berpendapat bahwa konflik
modern cenderung bersifat intra-state, dan dipamahi dalam empat
variabel prekondisi konflik.2
Pertama, konflik diakibatkan oleh adanya communal content, yaitu
unit analisa yang menjadi fokus pada PSC dengan melihat identity group
– misalnya kelompok ras, agama, etnik, budaya, dan sebagainya.
Dalam hal ini, hubungan antara identity group dengan negara yang
1 Adward Azar dalam Oliver Ramsbotham, “The Analysis of Protracted SocialConflict: A Tribute to Edward Azar,” Review of International Studies 31 (2005): 113.2 Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, Contemporary Conflict Resolution: thePrevention, Management, and Transformation of Deadly Conflicts 2nd edition (Cambridge: PolityPress, 2005), 85-88.
3
menjadi inti permasalahannya, dan bagaimana kepentingan dan
kebutuhan individu dimediasikan melalui kelompok sosial.
Kedua, menganalisa adanya perampasan akan kebutuhan dasar
manusia. Keluhan masyarakat akibat kekurangan kebutuhan biasanya
diekspresikan secara kolektif, dan kegagalan negara dalam merespon
keluhan tersebut membuat konflik semakin berlarut-larut. Dalam hal
ini, ‘kebutuhan’ bersifat ontologi dan non-negotiable, yang mencakup
kebutuhan akan keamanan, kemudahan ekonomi, dan kebebasan.
Sehingga apabila konflik terjadi, maka akan cenderung bersifat
intens, kejam, dan irasional.
Ketiga, pemerintahan dan peran negara berperan besar dalam
memberikan satisfaction atau frustation bagi kebutuhan individu atau
identity group. Sebagian besar negara yang mengalami PSC cenderung
dianggap sebagai pemerintahan yang parokial, otoriter, dan rapuh
yang gagal dalam menyediakan kebutuhan dasar manusia. Keempat,
adalah international linkages. Hal ini mengacu pada pemahaman bahwa
negara modern, khususnya weak state, rentan akan kekuatan
internasional yang bergerak sebagai global community yang ikut serta
dalam permasalahan sosial dan politik domestik, dan memiliki
pengaruh besar terhadap posisi dan peran negara dalam sistem
internasional.
Terpenuhinya keempat variabel menurut Azar kemudian tidak
semerta-merta menimbulkan konflik yang dijelaskan dalam PSC,
dimana Ia juga menambahkan terdapat faktor lain yang menjadi
inisiasi akan suatu konflik. Hal tersebut adalah aksi dan strategi
komunal, aksi dan strategi negara, serta mekanisme konflik.3
Lebih lanjut, Azar berpendapat bahwa PSC cenderung banyak
terjadi di negara-negara berkembang. Hal ini biasanya ditandai
3 Miall, Ramsbotham, dan Woodhouse, Contemporary Conflict Resolution, 87.
4
dengan negara yang memiliki pertumbuhan populasi cepat dan
keterbatasan rosurce base, memiliki keterbatasan kapasitas politik,
tradisi hierarki, aturan birokratik yang metropolitan centres, serta
adanya represi politik.4
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Sejarah Penyebab Konflik di Sri Lanka
Perang sipil Sri Lanka merupakan konflik yang berawal pada 23
Juni 1983, dengan munculnya kelompok Gerakan Pejuang Pembebasan
Macan Tamil (Liberation Tigers of Tamil Eelam/LTTE) atau yang biasa juga
4 Miall, Ramsbotham, dan Woodhouse, Contemporary Conflict Resolution, 87.
5
disebut Macan Tamil (Tamil Tigers). LTTE merupakan organisasi militan
independen yang berjuang mendirikan negara Tamil yang disebut
“Tamil Eelam” di wilayah Utara dan Timur Sri Lanka. Setelah 26
tahun konflik berjalan, militer Sri Lanka menyatakan kemenangannya
atas LTTE pada Mei 2009, membawa perang sipil berakhir.5
Konflik Sri Lanka dapat dianggap sebagai contoh konflik yang
sangat kompleks, dimana konflik etnis, ekonomi, politik, budaya,
dan agama telah memicu pemberontakan dan tindak kekerasan. Adapun,
akar penyebab gerakan yang diinisiasi oleh LTTE disebabkan
beberapa faktor yang terjadi sejak masa kolonial Inggris. Secara
historis, hal ini erat kaitannya dengan kepentingan dan konflik
etnis antara Sinhala sebagai mayoritas di Sri Lanka (82% dari
total penduduk per 2001), dengan Tamil yang merupakan masyarakat
minoritas (9,4%).6
Pasca kemerdekaan dari kolonial Inggris pada 1948, kebangkitan
nasionalis oleh Sinhala terjadi dengan tujuan mengembalikan bahasa
lokal, budaya, dan agama yang telah ditekan selama pemerintahan
kolonial. Kebangkitan ini terjadi tidak hanya terhadap
kolonialisme Inggris, tapi juga terhadap etnis Tamil yang telah
menikmati posisi istimewa selama masa kolonial.7 Tepat setelah
kemerdekaan, Parlemen Ceylon8 mengeluarkan regulasi yang disebut
sebagai “Akta Kewarganegaraan Ceylon”, yang memberikan bentuk
diskriminasi pertama bagi minoritas Tamil dengan membuat mereka5 Asoka Bandarage, The Separatist Conflict in Sri Lanka Terrorism, Ethnicity, Political Economy, (New York: Routledge, 2009), 1. 6 Jayshree Bajoria, “The Sri Lankan Conflict,” Council on Foreign Relations, http://www.cfr.org/terrorist-organizations-and-networks/sri-lankan-conflict/p11407 (diakses pada 2 Juni 2014).7 Camilla Orjuella, “Building Peace in Sri Lanka: A Role for Civil Society,” Journal of Peace Research, no. 2 (2003): 198. 8 Ceylon adalah nama yang merujuk pada wilayah Sri Lanka sejak masa pendudukan koloni Belanda di Sri Lanka, sebelum akhirnya Ceylon berubah menjadi Sri Lanka pada 1972, bersamaan dengan ditetapkannya Budha sebagai agama utama di negara tersebut.
6
hampir tidak mungkin mendapatkan hak warganegara. Sekitar lebih
dari 700.000 warga Tamil dibuat stateless. Selama tiga dekade
berikutnya, lebih dari 300.000 warga Tamil dideportasi kembali ke
India.9 Pada 1956, Perdana Menteri S. W. R. D. Bandaranaike
mengeluarkan “Sinhala Only Act”, yaitu sebuah aturan yang mengubah
bahasa Inggris menjadi bahasa Sinhala sebagai bahasa nasional. Hal
ini kemudian dianggap sebagai bentuk diskriminasi lain bagi Tamil
untuk mencegah mereka bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan
layanan publik lainnya. Masyarakat berbahasa Tamil menilai aturan
ini sebagai diskriminasi linguistik, budaya, dan ekonomi terhadap
mereka. Banyak dari masyarakat berbahasa Tamil dipaksa untuk
mengundurkan diri karena tidak fasih berbahasa Sinhala. Hal ini
menjadi pemicu awal kerusuhan Gal Oya pada 1956 dan 1958.10 Adapun,
peta persebaran wilayah dengan penduduk berbahasa Tamil dapat
dilihat pada gambar berikut.
9 Anne Noronha Dos Santos, Military Intervention and Secession in South Asia: the Cases of Bangladesh, Sri Lanka, Kashmir, and Pubjab, (Connecticut: Praeger Security International, 2007), 45. 10 Anne Noronha Dos Santos, Military Intervention and Secession in South Asia: the Cases of Bangladesh, Sri Lanka, Kashmir, and Pubjab, 43-44.
7
Dari peta tersebut, terlihat bahwa wilayah Utara Sri Lanka
merupakan wilayah yang di dominasi oleh masyarakat berbahasa
Tamil. Hal ini erat kaitannya dengan letak geografis Sri Lanka
yang berbatasan langsung dengan India di bagian Utara, yaitu
negara asal masyarakat Tamil Sri Lanka. Undang-undang “Akta
Kewarganegaraan Ceylon” dan “Sinhala Only Act” memberikan ruang
yang semakin terbuka bagi masyarakat Sinhala untuk aktif dalam
politik dan menduduki jabatan pemerintahan. Hal ini terlihat dari
kursi parlemen yang diisi oleh 80 persen etnis Sinhala, dimana
kecenderungan ini terus berlanjut, mengarahkan Parlemen Sri Lanka
lebih dilihat sebagai “Dewan Sinhala”.11
Selanjutnya, pada tahun 1970, kebijakan standarisasi dalam
sektor pendidikan perguruan tinggi dijalankan. Melalui kebijakan
ini, standar penerimaan universitas diberlakukan untuk memperbaiki
11 Anne Noronha Dos Santos, Military Intervention and Secession in South Asia: the Cases of Bangladesh, Sri Lanka, Kashmir, and Pubjab, 45.
8
Sumber: Edgar O’Ballance,The Cyanide War: Tamil Insurrection in Sri Lanka 1973-1988 (London: Brassey’s,
jumlah proporsional terhadap mahasiswa Tamil di Sri Lanka. Secara
resmi, kebijakan itu dimaksudkan untuk mengurangi jumlah mahasiswa
Tamil di berbagai universitas, yang selama beberapa tahun
belakangan justru mendominasi, khususnya di ilmu-ilmu alam yang
dianggap krusial dalam pembangunan negara. Hal ini membuat
masyarakat etnis Sinhala “kalah saing”. Oleh sebab itu,
Universitas Ceylon menerapkan standar nilai sebesar 250 dari total
nilai 400 bagi calon mahasiswa Tamil yang ingin masuk ke fakultas
IPA, dan nilai 229 untuk etnis Sinhala.12 Aturan ini menyebabkan
jumlah mahasiswa Tamil yang masuk ke perguruan tinggi khususnya
pada program IPA menurun drastis.13 Bentuk lain dari diskriminasi
yang dijalankan pemerintah adalah melalui dukungan kolonisasi
terhadap wilayah tradisional Tamil oleh para petani Sinhala,
pelarangan impor media berbahasa Tamil, dan penetapan Budha
sebagai agama utama pada 1978. Dalam hal ini, Budha merupakan
agama yang mayoritas dipegang oleh etnis Sinhala, sedangkan Tamil
mayoritas beragama Hindu dan Kristen.14
Pada bulan Mei 1981, pemerintah melalui polisi dan militer
membakar perpustakaan Jaffna15, mengakibatkan kerusakan lebih dari
90.000 buku, termasuk gulungan perkamen yang menjadi nilai sejarah
bagi etnis Tamil. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu titik
balik utama dalam meyakinkan warga Tamil bahwa pemerintah tidak
12 Asoka Bandarage, The Separatist Conflict in Sri Lanka Terrorism, Ethnicity, Political Economy, 53-54.13 Nira Wickremasinghe, Sri Lanka in the Modern Age: A History of Contested Identities. (Honolulu, University of Hawaii Press, 2006), 32.14 Red Pepper, “Background to Brutality,” Red Pepper, http://www.redpepper.org.uk/Background-to-brutality/ (diakses pada 1 Juni 2014).15 Jaffna adalah ibukota provinsi Sri Lanka Utara. Pada masa Perang Sipil, Jaffna merupakan kota kedua terbesar di Sri Lanka, setelah Kolombo.
9
bisa melindungi mereka atau warisan budayanya, sehingga semakin
menguatkan alasan untuk melalukan gerakan separatisme.16
Segala kebijakan diatas mengarahkan Sri Lanka untuk menjadi
Negara Sinhala, yang mana masyarakat minoritas kemudian merasa
dianaktirikan. Oleh karena itu, etnis Tamil kemudian melakukan
berbagai protes, yang berawal dari proses non-kekerasan. Namun
pada akhir 1970-an, semakin banyak kelompok militan muncul yang
tidak menuntut kesamaan hak dalam negara Sri Lanka, melainkan
berjuang untuk membangun negara sendiri dan hak menentukan nasib
sendiri (self-determination).17 Salah satu kelompok militan ini bernama
LTTE, yaitu salah satu aktor utama dalam konflik berkepanjangan
Sri Lanka. Puncaknya, pada tahun 1983, 13 tentara pemerintah
terbunuh atas penyerangan LTTE, yang kemudian menimbulkan skeptis
anti-Tamil. Peristiwa ini menjadi awal mula konflik, yang disebut
sebagai “Perang Eelam Pertama”.18
2.2 Pecahnya Perang Sipil Sri Lanka
Berangkat dari berbagai permasalahan dan diskriminasi
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pemuda Tamil di
bagian Utara dan Timur Sri Lanka membentuk kelompok-kelompok
militan. Kelompok ini dibentuk secara independen dari kepemimpinan
Colombo Tamil. Dalam hal ini, militan paling menonjol adalah
kelompok Tamil New Tigers (TNT) yang dibentuk pada 1972. Dalam
perkembangannya, TNT mengubah nama menjadi LTTE, yang kemudian
16 Camilla Orjuella, “Building Peace in Sri Lanka: A Role for Civil Society,” Journal of Peace Research, 67.17 Sri Lanka Campaign: For Peace & Justice, “History of Conflict,” Sri Lanka Campaign, http://www.srilankacampaign.org/historyoftheconf.htm (diakses pada 1 Juni 2014)18 Neil DeVotta, “Control Democracy, Institutional Decay, and the Quest for Eelam: Exploring Ethnic Conflict in Sri Lanka,” Pacific Affairs, no. 1 (2000): 56.
10
dikenal sebagai militan utama yang terlibat dalam pecahnya perang
sipil Sri Lanka. Operasi besar pertama yang dijalankan oleh LTTE
adalah pembunuhan walikota Jaffna, yaitu Alfred Duraiappah pada
tahun 1975.19
Modus operandi yang dijalankan oleh LTTE adalah pembunuhan
elit-elit pemerintah, dimana setelah peristiwa 1975, pembunuhan
kembali dijalankan oleh pemimpin LTTE terhadap M. Canagaratnam
sebagai anggota parlemen pada 1977. Pada 23 Juli 1983, LTTE
meluncurkan serangan mematikan ke markas tentara Sri Lanka di luar
kota Thirunelveli, menewaskan seorang perwira dan 2 prajurit. Hal
ini menjadi titik awal konflik dimulai, dimana pemerintah
menanggapi dengan sentimen “nasionalisme”nya untuk melalukan
serangan balik dan pembantaian di Kolombo dan berbagai wilayah
lain, yang diperkirakan menyebabkan 3.000 warga Tamil tewas.
Selain itu, masyarakat Sri Lanka yang mulai skeptis dan anti-Tamil
melakukan pembakaran pada bisnis-bisnis yang dimiliki oleh warga
Tamil, khususnya di Kolombo.20
Selanjutnya, kekerasan terus terjadi pada tahun-tahun
berikutnya. pada 1984, LTTE melakukan penyerangan dan pembantaian
di Kent and Dollar Farm, mengakibatkan ribuan warga yang sedang
tertidur dibunuh dengan kapak di kepala. Kemudian pembantaian
Anuradhapura pada 1985, dilakukan dengan penembakan dan membunuh
146 warga sipil dalam kuil Budha Jaya Sri Maha Bodhi. Terkait hal
ini, pemerintah kemudian merespon balik dengan menggunakan perahu
Kumudini dimana lebih dari 23 warga sipil Tamil tewas. Seiring
waktu, LTTE semakin berkembang dengan melakukan gabungan dengan
kelompok militan Tamil lainnya. Namun di sisi lain, warga etnis
19 Asoka Bandarage, The Separatist Conflict in Sri Lanka Terrorism, Ethnicity, Political Economy, 1. 20 Paul A. Povlock, “A Guerilla War at Sea: The Sri Lankan Civil War,” Small Wars Journal, (2011): 9
11
Tamil yang tidak setuju dengan tindak kekerasan yang dilancarkan
LTTE memilih untuk pro dengan pemerintah, untuk tergabung dalam
militer maupun politik, yang pada intinya menentang visi LTTE
untuk mendirikan negara independen.21
Upaya pembicaraan damai antara pemerintah dan LTTE mulai
dilakukan di Thimphu pada 1985, namun sesaat setelahnya upaya
tersebut gagal dan perang berlanjut. Sepanjang Mei-Juni 1987,
militer Sri Lanka melancarkan operasi ofensif yang disebut
“Operasi Pembebasan” atau “Vadamarachchi Operation”, untuk
meningkatkan kontrolnya di wilayah Jaffna dari pihak LTTE. Operasi
ini menjadi tindakan ofensif pertama yang menandai perang
konvensional Sri Lanka sejak masa kemerdekaan. Operasi itupun
berhasil, namun pemimpin LTTE, Prabhakaran lolos dari
penyerangan.22
Kekerasan antara pemerintah dan LTTE terus berlanjut selama
puluhan tahun, menyebabkan ratusan ribu korban meninggal,
kerusakan di berbagai infrastruktur, dan permasalahan sosial
lainnya. Setiap kali pemerintah Sri Lanka mencoba menekan Tamil,
pergoalakan konflik menjadi lebih kuat. Selama periode 1983-2009,
setidaknya perang sipil Sri Lanka sampai pada “Perang Eelam
Keempat” pada tahun 2006.23 Selain itu, konflik antara pemerintah
Sri Lanka dan LTTE menjadi perang sipil yang paling lama terjadi
di Asia, bertahan selama kurang lebih 26 tahun.24 Akibat berbagai
penyerangan, teror, dan pembunuhan yang dijalankan, LTTE kemudian21 Sri Lanka Campaign: For Peace & Justice, “History of the Conflict,” http://www.srilankacampaign.org/historyoftheconf.htm.22 Asoka Bandarage, The Separatist Conflict in Sri Lanka Terrorism, Ethnicity, Political Economy, 15.23 Reuters, “TIMELINE: Sri Lanka’s 25-Year Civil War,” Reuters, http://www.reuters.com/article/2009/05/17/us-srilanka-war-timeline-sb-idUSTRE54F16620090517 (diakses pada 2 Juni 2014).24 A.J.V. Chandrakanthan, “Eelam Tamil Nationalism: an Inside View,” dalam Sri Lankan Tamil Nationalism: Its Origin and Development in the 19th and 20th Centuries, ed. A. Jeyaratnam Wilson (Canada: UBC Press, 2000), 158.
12
dianggap sebagai kelompok teroris oleh banyak negara. Namun
sebaliknya, tindakan yang dijalankan oleh pemerintah terhadap
etnis Tamil juga dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan, dimana
serangan terhadap warga Tamil pada 1983 digambarkan dalam laporan
Mahkamah Internasional sebagai kekerasan yang sebanding dengan
tindak genosida.25 Adapun, selama konflik berlangsung, keterlibatan
aktor eksternal seperti India, Norwegia, Amerika Serikat, dan
Jepang mewarnai konflik yang terjadi. Setelah proses escalation-
descalation yang panjang selama puluhan tahun, pada Mei 2009
pemerintah akhirnya mengumumkan kemenangannya atas LTTE. Pemimpin
LTTE, Velupillai Prabhakaran, dinyatakan tewas dan kelompok
tersebut menyatakan langkah penurunan senjata.26
2.3 Analisis Perang Terbuka Selama Konflik Sri Lanka
Dalam pergolakan konflik yang terjadi di Sri Lanka, terdapat
banyak pembelajaran yang dapat dipetik sebagai modal analisa dalam
tulisan ini, khususnya menurut kacamata teori Protracted Social Conflict
(PSC). Dalam teori tersebut, konflik dipahami sebagai bentuk
kekerasan yang berkepanjangan, violent struggle, dan melibatkan
kelompok komunal. Adapun hal ini dikarenakan terbatasnya pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat kebutuhan dasar yang meliputi keamanan,
pengakuan, penerimaan, dan akses yang adil. Apabila dilihat dalam
konteks konflik di Sri Lanka, maka hal-hal yang disebutkan dalam
PSC sangat tergambarkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan,
konflik Sri Lanka berawal pada konflik kepentingan antara etnis
Sinhala dan Tamil yang meliputi hampir seluruh aspek kehidupan.
Berawal dari akses politik yang dikuasai oleh Sinhala sejak 1948,25 Yoki Rakaryan Sukarjaputra, Auman terakhir Macan Tamil: Perang Sipil Sri Lanka 1976-2009 (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), 97-9826 Camilla Orjuella, “Building Peace in Sri Lanka: A Role for Civil Society,” Journal of Peace Research, 199.
13
Tamil kemudian menjadi pihak yang “dianaktirikan” melalui
kebijakan-kebijakan yang cenderung menyulitkan masyarakat Tamil.
Adapun regulasi yang tercantum dalam Akta Kewarganegaraan Ceylon
menjadi faktor awal yang memicu ketegangan terjadi. Dalam konteks
Sri Lanka, seluruh penyebab konflik yang disampaikan saling
terkait satu sama lain, yang secara kumulatif memicu eskalasi
kelompok komunal untuk menentang pemerintah.
Upaya pemerintah untuk “mengembalikan” bahasa lokal, budaya,
dan agama yang telah ditekan selama pemerintahan kolonial pada
akhirnya hanya menjadikan etnis non-Sinhala sulit mendapatkan
akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pengakuan, penerimaan,
akses yang adil, dan keamanan. Hal-hal seperti pemberlakuan
“Sinhala Only Act” yang mengatur bahasa nasional menjadikan
masyarakat non-Sinhala termarjinalkan, khususnya warga Tamil. Dari
sini, terlihat bahwa pembangunan negara pasca kemerdekaan yang
dijalankan oleh pemerintah justru menimbulkan masalah baru yang
berujung pada perang sipil. Adapun, hal ini menggambarkan tentang
bagaimana situasi perang konvensional, dimana konflik tidak lagi
banyak terjadi antarnegara, melainkan di dalam negara yang
cenderung melibatkan kelompok etnis. Selain itu, penjelasan Azar
yang menyatakan bahwa konflik modern cenderung terjadi di negara
berkembang terlihat pula dalam kasus ini. Hal tersebut tidak lain
dikarenakan negara-negara berkembang cenderung instabil pasca
peninggalan pemerintah kolonial dan “gagap” terhadap sistem
kekuasaan yang telah lama dipegang oleh pihak asing. Apabila
ditelusuri dalam literatur, pernyataan ini sesuai dengan pemikiran
Nye mengenai konflik kontemporer.27
27 Joseph S. Nye, Understanding International conflicts,: An Introduction to Theory and History, (NewYork: Pearson Longman, 2009), 164.
14
Terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar khususnya akses yang
adil, pemerintahan Sri Lanka pasca kemerdekaan telah sangat
membatasi akses yang adil bagi sebagian masyarakat yang berada di
wilayahnya. Meski tidak secara eksplisit, namun pemberlakuan
Sinhala Only Act berakibat pada terbatasnya ruang gerak dan
partisipasi masyarakat non-bahasa Sinhala dalam karir, terutama
politik. Dalam pemerintahan Sri Lanka, berbahasa Sinhala secara
fasih merupakan syarat penting. Oleh karena itu, kesempatan karir
politik dan ekonomi di Sri Lanka pada akhirnya hanya mengarah
kepada hanya sebagian kelompok masyarakat. Selain itu, terkait
kebutuhan pengakuan dan penerimaan, lagi-lagi hal ini sangat
terbatas bagi warga Tamil. pengakuan warganegara dan penerimaan
etnis Tamil sebagai bagian dari Sri Lanka menjadi harta yang harus
dikejar melalui perang. Pada akhirnya, identifikasi ciri konflik
berkepanjangan dalam teori PSC terlihat dari berbagai pemicu
perang sipil di Sri Lanka.
Adapun penyebab konflik yaitu communal content dalam teori PSC
terlihat dalam konflik kepentingan antara Sinhala dan Tamil.
Sinhala, sebagai etnis asli wilayah Sri Lanka yang mayoritas
beragama Budha, menjadi pihak yang banyak merepresi masyarakat
Tamil, yang mana tindakan-tindakan tersebut dilegitimasi melalui
pemerintahan. Dalam konteks tertentu, hal ini tidak dapat
disalahkan sepenuhnya terhadap Sinhala atau pemerintah, karena
pada dasarnya pemerintah memiliki legitimasi dan justifikasi
terhadap tindakan yang diambil, khususnya terkait kondisi internal
negara. Di sisi lain, pemberontakan oleh kelompok-kelompok
militan, khususnya LTTE merupakan wujud akumulasi kepentingan dan
kebutuhan individu yang dimediasikan melalui kelompok. Dalam hal
ini, Prabhakaran sebagai pemimpin LTTE adalah yang paling berperan
15
dalam mengumpulkan kekuatan militan. Oleh karena itu, saat aturan
dan sikap pemerintah terhadap pihak tertentu dirasa merugikan dan
bahkan mendiskriminasi, maka terjadilah pemberontakan untuk
merevisi sistem yang ada, atau bahkan memisahkan diri sepenuhnya
untuk kemudian menentukan nasib sendiri, terlepas dari
pemerintahan yang ada. Dalam kasus konflik antara pemerintah Sri
Lanka dan LTTE, sejak awal LTTE tidak berusaha merevisi sistem dan
kondisi yang ada, melainkan memang bertujuan melakukan gerakan
separatis dan pengakuan terhadap wilayah klaimnya.
Pernyataan diatas kemudian mengarah pada fakta lain, bahwa
saat negara telah mencapai tahap frustation dalam memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat atau pihak tertentu di wilayahnya, hal ini
mengakibatkan konflik semakin berlarut-larut dan perang yang
terjadi pun bersifat intens, kejam, dan irasional. Hal tersebut
terlihat dari bagaimana pada awalnya LTTE tidak melakukan dialog
atau bentuk komunikasi lain dalam menyelesaikan masalah, melainkan
langsung melancarkan tindak pembunuhan terhadap walikota Jaffna,
yang diikuti oleh pembunuhan dan pembantaian lainnya. Di sisi
lain, tindakan serupa justru menjadi respon balik pemerintah, yang
malah membalas peristiwa-peristiwa tersebut dengan cara
pembantaian terhadap masyarakat sipil Tamil dan menyebabkan ribuan
korban meninggal. Hal ini tentu menyalahi hak asasi manusia oleh
keduanya, dan sebagaimana yang telah dikatakan, konflik yang
terjadi pada akhirnya bersifat balas-membalas dan cenderung
semakin parah dalam perkembangannya—mengakibatkan konflik semakin
berlarut-larut.
Meski dalam tulisan ini hanya sedikit menyinggung keterlibatan
aktor internasional, namun bukan berarti konflik di Sri Lanka
terbebas dari ikut campur pihak eksternal. Melainkan, sejak awal
16
konflik terjadi, keterlibatan India sebagai negara tetangga yang
memiliki hubungan budaya dan kepentingan dengan masyarakat Tamil
mewarnai konflik yang ada. Bahkan, India sempat memihak kedua
pihak di waktu yang berbeda. Selain itu, keterlibatan Norwegia
juga menjadi hal yang perlu dipahami, dimana Norwegia pada 2002
berhasil menjadi mediator dalam pembicaraan perdamaian antara
pemerintah dan LTTE. Namun karena keterbatasan dalam tulisan ini,
maka hal-hal tersebut tidak banyak disinggung, karena fokus dalam
tulisan ini sendiri adalah penyebab dan awal konflik yang kemudian
di analisa dengan teori PSC.
BAB III
KESIMPULAN
Pada kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa gambaran secara umum
penyebab konflik yang terjadi di Sri Lanka adalah akibat adanya
ketidaksetaraan sikap pemerintah terhadap masyarakat di Sri Lanka,
khususnya terhadap masyarakat etnis Tamil yang di eksklusi karena
dianggap “berbeda” dengan budaya lokal yang selalui dikaitkan
dengan etnis Sinhala sebagai dominan. Pada kenyataannya, aturan-
aturan yang dijalankan oleh pemerintah cenderung menyulitkan etnis
Tamil untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar, seperti
keamanan, pengakuan, penerimaan, dan akses yang adil (meliputi
akses terhadap politik dan ekonomi). Akibat akumulasi konfliktual
kepentingan antar keduanya, masyarakat Tamil kemudian menginisiasi
berbagai pergerakan anti-pemerintah sebagai protes ketidaksetaraan
tersebut. Hal ini diikuti dengan semakin berkembangnya
ketidakpuasan mayoritas masyarakat Tamil terhadap pemerintah Sri
Lanka, yang membawa aksi perlawanan semakin besar dan berujung
17
pada gerakan separatis dan bentuk direct violence yang semakin brutal.
Puncaknya, salah satu kelompok militan yang bernama LTTE yang
mendominasi gerakan anti-pemerintah melakukan penyerangan,
pembunuhan, dan pembantaian terhadap pihak-pihak pemerintah dan
sipil, membawa konflik terbuka dan terjadi berlarut-larut selama
26 tahun. Hal ini tidak lain dikarenakan aksi-aksi yang dijalankan
oleh LTTE justru mendapat respon balik yang dapat dikatakan serupa
oleh pemerintah, mengakibatkan penyelesaian konflik semakin sulit
tercapai.
Daftar Pustaka
Sumber Tulis
Azar, Adward, “The Analysis of Protracted Social Conflict: A
Tribute to Edward Azar,” Review of International Studies 31, ed. Oliver
Ramsbotham (2005): 113.
Bandarage, Asoka. The Separatist Conflict in Sri Lanka Terrorism, Ethnicity, Political
Economy. New York: Routledge, 2009.
Chandrakanthan, A.J.V. “Eelam Tamil Nationalism: an Inside View,”
dalam Sri Lankan Tamil Nationalism: Its Origin and Development in the 19th and
20th Centuries, ed. A. Jeyaratnam Wilson. Canada: UBC Press, 2000.
DeVotta, Neil. “Control Democracy, Institutional Decay, and the
Quest for Eelam: Exploring Ethnic Conflict in Sri Lanka,” Pacific
Affairs, no. 1 (2000): 55-76.
Dos Santos, Anne Noronha. Military Intervention and Secession in South Asia: the
Cases of Bangladesh, Sri Lanka, Kashmir, and Pubjab. Connecticut: Praeger
Security International, 2007.
18
Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse. Contemporary
Conflict Resolution: the Prevention, Management, and Transformation of Deadly
Conflicts, 2nd edition. Cambridge: Polity Press, 2005.
Nye, Joseph S. Understanding International conflicts,: An Introduction to Theory and
History. New York: Pearson Longman, 2009.
O’Ballance, Edgar. The Cyanide War: Tamil Insurrection in Sri Lanka 1973-1988.
London: Brassey’s, 1989.
Orjuella, Camilla. “Building Peace in Sri Lanka: A Role for Civil
Society.” Journal of Peace Research, no. 2 (2003): 195-212.
Povlock, Paul A. “A Guerilla War at Sea: The Sri Lankan Civil
War,” Small Wars Journal, (2011): 1-51.
Sukarjaputra, Yoki Rakaryan. Auman terakhir Macan Tamil: Perang Sipil Sri
Lanka 1976-2009. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
Wickremasinghe, Nira. Sri Lanka in the Modern Age: A History of Contested
Identities. Honolulu, University of Hawaii Press, 2006.
Sumber Elektronik
Bajoria, Jayshree. “The Sri Lankan Conflict,” Council on Foreign
Relations, http://www.cfr.org/terrorist-organizations-and-
networks/sri-lankan-conflict/p11407 (diakses pada 2 Juni 2014).
Red Pepper, “Background to Brutality,” Red Pepper,
http://www.redpepper.org.uk/Background-to-brutality/ (diakses
pada 1 Juni 2014).
Reuters, “TIMELINE: Sri Lanka’s 25-Year Civil War,” Reuters,
http://www.reuters.com/article/2009/05/17/us-srilanka-war-
timeline-sb-idUSTRE54F16620090517 (diakses pada 2 Juni 2014).
Sri Lanka Campaign: For Peace & Justice, “History of Conflict,”
Sri Lanka Campaign,
19