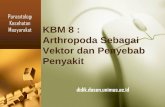MULTIKULTURAL (Kajian holistik tentang Multicultural dari berbagai dimensi)
Transcript of MULTIKULTURAL (Kajian holistik tentang Multicultural dari berbagai dimensi)
MULTIKULTURAL (Kajian holistik tentang Multicultural dari berbagai dimensi)
Sadar atau tidak sadar, bangsa Indonesia sedang mengalami perubahan yang cukup besar untuk memasuki babakan baru dalam ketatanegaraannya. Tidak kurang berbagai strategi kebijakan dan implementasinya dilakukan olah para pemimpin negara tercinta ini, mulai dari era Sukarno sampai dengan putrinya yakni Megawati Sukarnoputri. Apa yang telah terjadi? masih saja terjadi kerusuhan yang diakibatkan oleh SARA. Untuk itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa kita perlu sepakat untuk menelaah secara kritis tentang multikultural, sebagai salah satu kenyataan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di sisi lain harus diakui bahwa arus global antar budaya dapat mempengaruhi perjalanan rakyat Indonesia dalam menghadapi peradaban masa depan.
Ancaman disintegrasi bangsa, arogansi kesukuan dapat terjadi pada era otonomi daerah, dan sejumlah fenomena budaya lainnya merupakan akibat dari kekeliruan strategi ketatanegaraan Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa sistem ketatanegaraan dalam memperkuat kebudayaan nasional kurang antisipatoris. Pendidikan yang berbasis multikultural kurang tertransformasi dengan baik ke setiap warga negara Indonesia.
Berkaitan dengan itu pendidikan yang berbasis multikultural seharusnya menjadi salah satu prioritas utama masa kini apabila kitaingin membangun bangsa yang kuat dan mandiri. Pendidikan berbasis multikultural, harus mampu menyangga multikultural kebangsaan yang genuine dan otentik. Proses pendidikan yang terselenggara melalui jalur sekolah, luar sekolah (masyarakat) ataupun keluarga, belum dapat menjawab epistomologi multikultural. Ketidakter-paduan antara kebijakan, konsep dan implementasi dalam pendidikan yang berbasis multikultural, dapat mengakibatkan tersendatnya perkembangan budaya nasional. Proses reformasi yang terjadi di Indonesia, dimana adanya transisi pada sistem ketatanegaraan yang dulu berorientasi pada sentralistik menjadi desentralisasi akan membawa berbagai konsekuensi. Penulis berkeyakinan bahwa salah satu konsekuensinya adalah kebijakan dan implementasi dari sistem pendidikan nasional perlu untuk dikaji ulang, khususnya perhatian yang serius tentang pendidikan yang berbasis multikultural.
Pertanyaan pokok sanggupkah kita bersaing di arena global yang bebasdalam perubahan yang begitu cepat ? Dalam kajian penulis terdapat 2 (dua) pandangan yang hidup dalam masyarakat kita yakni masyarakat yang pesimis dan optimis. Masyarakat yang pesimis melihat abad yang akan menyongsong mereka sebagai sesuatu yang menakutkan, sebab kita
memiliki sumber daya yang berkualitas rendah, dan juga terhambat oleh persoalan multikultural yang cenderung sebagai suatu persoalan bangsa saja.
Sedangkan bagi masyarakat yang optimis, melihat apa yang telah dicapai bangsa Indonesia ini merupakan modal yang sangat berharga untuk memasuki persaingan global. Mereka menganggap multikultural bangsa Indonesia sebagai sesuatu modal penggerak untuk menuju pembaharuan yang lebih maju. Prestasi putra-putri Indonesia dalam berbagai pertandingan atau kompetisi internasional bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menunjukan adanya prestasi yang cukup menggembirakan. Mereka dapat bersaing dengan para peserta dari negara-negara yang terlebih dahulu disebut sebagai negara maju. Dalam konteks ini kebudayaan sebagai proses dialog antara yang ada dan tantangan yang dihadapi dalam membentuk dirinya untuk menghadapidinamika tantangan dan peluang di masa depan.
Proses multikultural itu berlangsung sebagai suatu kenyataan alamiahdan sesuatu yang dinamis-historis dan bagaimana pula ia diperlakukanketika menjadi pengambil berbagai kebijakan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masalah penting untuk dicermati, ditelaah, dan disikapi. Seiring dengan itu pada era otonomi daerah, tuntutan masyarakat yang sangat beragam berkaitan dengan politik, ekonomi, hukum dan sebagainya. Dalam konteks ini, apa yang ditampilkan oleh masyarakat dalam kelompoknya menunjukan adanya multikultural bangsa.
Dalam rangka menghadapi masa depan yang lebih kompleks, dimana persaingan antara negara akan lebih dikedepankan, menyebabkan tuntutan solidaritas dan kerukunan masyarakat bangsa sangat diperlukan. Oleh karena itu, menelaah secara holistik tentang multikultural menjadi kajian yang strategis dan penting bagi bangsa Indonesia
B. Struktur Masyarakat Indonesia dan Masalah Multikultural
Sebuah kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari kolektifitas kelompok-kelompok masyarakat yang bersifat majemuk. Dari segi etnitasnya terdapat 656 suku bangsa (Hidayat, 1997) dengan tidak kurang dari 300 jenis bahasa-bahasa daerah, dan di Irian Jaya saja lebih 200 bahasa-bahasa sukubangsa (Koentjaraningrat,1993). Penduduknya sudah mencapai 200 juta, yang menempatkan Indonesia padaurutan keempat dunia.
Tatanan dan sejarah pembentukannya memiliki arti strategik, dilihat dari geopolitik perkembangan bangsa-bangsa di dunia, khususnya Asia
Tenggara. Salah sati ciri benua maritim Indonesia, lautannya mengandng suber daya alam yang kaya. Demikian juga wilayah pesisirnya, dimana hgaris pentainya sepanjang 81.000 km itu beranekaragam dan sangat besarpotensi budidaya laut. Geografi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki keunikan budaya, terlebih jika dikaitkan dengan letah dalam peta dunia.
Wilayah lingkungan utama kehidu-pannya juga memperlihatkan variasi yang berbeda-beda. Ada komunitas yang mengandalkan pada laut sebagaisumber kehidupannya seperti orang Bajo. Orang-orang Bugis-Makasar, Bawean, dan Melayu dikenal sebagai masyarakat pesisir; serta terdapat pula komunitas-komunitas pedalaman, antara lain orang Gayo di Aceh, Tengger di Jawa Timur, Toraja di Sulawesi Selatan, Dayak diKalimantan, dan lain sebagainya. Karakter pluralistik itu ditambah lagi dengan perbedaan-perbedaan tipe masyarakatnya. Sesung-guhnya multikultural tersebut sebagai suatu keadaan obyektif yang dimiliki bangsa Indonesia. Tetapi kemajemukan itu tidak menghalangi keinginanuntuk bersatu! Paling tidak, beberapa daerah yang tergolong “termaginalkan” yang sempat kami kunjungi pada rentang tahun 1999 - 2002 untuk proses pendi-dikan masyarakatnya, adanya suatu harapan untuk berpikir maju, walaupun dengan tataran yang masih sederhana.
Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa pada tahun 1928, ikrar “Sumpah Pemuda” menegaskan tekad untuk membangun nasional Indonesia.Mereka bersumpah untuk berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu yaitu Indonesia. Ketika merdeka dipilihnya bentuk negara kesatuan. Kedua peristiwa sejarah ini menunjukan suatu kebutuhan yang secara sosio-politis merefleksi keberadaan watak pluralisme tersebut. Kenyataan sejarah dan sosial budaya tersebut lebih diperkuat lagi melalui ari simbol “Bhineka Tunggal Ika” yaitu “berbeda-beda dalam kesatuan” pada lambang negara Indonesia.
Struktur masyarakat Indonesia sebagaimana telah kita ketahui dapat menimbulkan persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi pada tingkat nasional. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis mencoba untuk menelaah kembali beberapa kharakteristik yang dapat kita kenali sebagai sifat dasar dari suatu masyarakat majemuk,sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasikun yakni; 1) terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan, atau lebih tepat sub-kebudayaan, yang berbeda satu sama lain; 2) memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat dasar; 3) kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar; 4) secara relatif seringkali terjadi konflik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain; 5) secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion)
dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; serta 6) adanya dominasi politik suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.
Oleh karena sifat-sifat demikian itulah, maka penulis beranggapan bahwa masyarakat majemuk tidak dapat digolongkan begitu saja, tanpa perhitungan analisis ke dalam salah satu diantara 2 jenis masyarakatmenurut model Emile Durkheim. Suatu masyarakat yang multikultural tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki unit-unit kekerabatan yang bersifat segmenter, akan tetapi sekaligus juga tidak dapat disamakan pula dengan masyarakat yang memiliki diferensiasi atau spesialiasi yang tinggi. Yang disebut pertama meru-pakan suatu masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam berbagai kelompok, yang biasanya berdasarkan garis keturunan tunggal, akan tetapi memiliki struktur kelembagaan yang homogeneous. Sedangkan yang disebut kedua, merupakan suatu masyarakat dengan tingkat diferensiasi fungsional yang tinggi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, akan tetapi bersifat komplementer dan saling tergantung satu sama lainnya. Di dalam keadaan demikian, solidaritasmekanis yang diikat oleh kesadaran kolektif maupun solidaritas organis yang diikat oleh saling ketergantungan di antara bagian-bagian dalam sistem sosial. Hal ini tidaklah mudah untuk ditumbuh-kembangkan dalam masyarakat yang multicultural.
Dalam konteks tersebut di atas, mengikuti pandangan fungsionalisme struktural untuk mewujudkan sistem sosial itu dapat terintegrasi dari berbagai multikultural terdapat 2 landasan pokok, yakni pertama, suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus diantara sebagian anggota masyarakat akan nilai-nilai kemasyara-katan yang bersifat fundamental. Kedua, suatu masyarakat senantiasa terintegrasi juga oleh karena berbagai anggota masyarakatsekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (cross-cutting affiliations). Oleh karena itu setiap konflik yang terjadi diantara suatu kesatuan sosial dengan kesatuan-kesatuan sosial yang lain segera akan dinetralisir oleh adanya masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial.
Pada tingkat tertentu keduanya mendasari terjadinya integrasi sosialdi dalam masyarakat yang bersifat majemuk. Oleh karena tanpa keduanya suatu masyarakat bagaimanapun tidak mungkin terjadi. (Nasikun, 2000). Akan tetapi sifat-sifat masyarakat majemuk sebagaimana yang kita uraikan di atas, telah menyebabkan landasan terjadinya integrasi sosial. Dalam hal ini sedikitnya ada dua macam konflik yang mungkin dapat terjadi yakni; 1) konflik di dalam tingkatannya yang bersifat ideologis, dan 2) konflik di dalam tingkatannya yang bersifat politis. Pada tingkatan ideologis bentuk konfliknya adanya pertentangan sistem nilai yang dianut di dalam
masyarakat tersebut. Sedangkan tingkatan politis bentuk konfliknya berupa pertentangan di dalam pembagian status kekuasaan, dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas di dalam masyarakat.
Di dalam situasi konflik akibat multikultural tersebut, pada umumnyasetiap pihak yang berselisih akan berusaha mengabadikan diri dengan cara memperkokoh solidaritas di antara sesama anggotanya. Dalam kaitan dengan sejarah, ternyata para kaum penjajah sengaja mempertantangkan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam budaya masyarakat Indonesia, sebagai upaya untuk mengikiskan persatuan dan kesatuan dari berbagai daerah. Jika tidak bersatu dan selalu dipertentangan pada demensi multikultural, maka negara penjajah akanmudah untuk mendikte bangsa Indonesia.
Dengan adanya struktur masyarakat Indonesia dan masalah multikultural, maka diperlukan kebijakan pemerintah yang menjamin kelangsungan hidup masyarakat, dengan cara tetap menghor-mati pranata, struktur, dan kebiasaan yang ada (social sustainability). Indonesia yang multikultural ini akan tetap bertahan sebagai sebuah negara kesatuan, apabila elemen-elemen pendukung kebersamaan tetap dipertahankan. Kecenderungan dominasi mayoritas (suku dan agama) harus ditata kembali agar rasa memiliki bangsa ini tidak luntur. Gejolak yang terjadi di berbagai daerah (Aceh, Kalimantan Tengah, Maluku, Irian Jaya, dan sebagainya), membutuhkan penanganan yang serius. Kelalaian tidak memperhatikan multikultural bangsa, di masa mendatang akan menjadi bom waktu yang sangat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
C. Hakikat Multikulural
Multikultural sebagai suatu konsep dan implementasi yang belum sepenuhnya disadari segenap warga masyarakat. Setiap manusia terlahir dalam keadaan berbeda satu sama lain, membawa sejumlah karakter fisik dan psikis yang berbeda. Di samping itu setiap individu memiliki sistem keyakinan, yang berbeda belum sepenuhnya bisa diterima dengan nalar kolektif masyarakat. Nalar kolektif masyarakat tentang multikultural masih terkooptasi logisentrisme, tafsir hegemonik yang sarat prasangka, curiga, kebencian, dan reduksi terhadap kelom-pok yang ada diluar dirinya. Tingkat pemahaman masyarakat Indonesia tentang multikultural sangat beragam.Namun demikian, pada mayoritas masyarakat Indonesia telah sadar akanpentingnya multikultural ini sebagai kekuatan bangsa, dan bukannya potensi untuk mencerai beraikan persatuan dan kesatuan.
Secara konseptual, M.G.Smith dalam Abdul Rachman (2001) mendefinisikan bahwa multikultural bangsa sebagai sesuatu yang lebih
dari hanya keragaman kebudayaan. Masyarakat yang benar-benar bersifat plural hanyalah apabila ada sesuatu keanekaragaman yang resmi (diakui) di dalam sistem dasar dari kelembagaan-kelembagaan yang diwajibkan. Kejelasan dari konsep M.G.Smith karena ia bertolak dari premis bahwa sistem kelembagaan apapun cenderung mengarah kepada integrasi dan kekentalan internal sementara setiap kelompok-kelompok yang berbeda akan cenderung membentuk suatu kesatuan sosialbudaya yang berdekatan.
Terlepas dari konteks wilayah dan zaman yang memang sangat berpengaruh munculnya sebuah konsep, namun kecenderungan adanya penyeragaman terhadap bermacam-macam suku bangsa. Kecenderungan ini akan menempatkan suku bangsa tertentu yang mayoritas sebagai unsur yang berhak mengatasnama dirinya “mewakili masyarakat”. Walau-pun pada kenyataannya dapat menimbulkan sikap primodial yang menguta-makan kepentingan suatu kelompok atau komunitas masyarakat tertentu.
Pada dasarnya manusia menciptakan budaya atau lingkungan sosial mereka sebagai suatu adaptasi terhadap lingkungan fisik dan biologismereka. Kebiasaan-kebiasaan, praktek-praktek, dan tradisi-tradisi untuk terus hidup dan berkembang diwariskan oleh suatu generasi ke generasi lainnya dalam suatu masyarakat tertentu. Pada gilirannya kelompok atau suku bangsa tersebut tidak menyadari dari mana asal warisan kebijaksanaan tersebut. Generasi berikutnya terkondisikan untuk menerima “kebenaran-kebenaran” tersebut tentang kehidupan di sekitar mereka, karena norma dan nilai tertentu telah ditetapkan oleh generasi sebelumnya. Namun demikian, norma dan nilai tertentu dari suatu daerah atau suku bangsa, dapat diterima atau tidak tergantung dari persepsi, pengetahuan dan keyakinan dari orang-orangyang bersangkutan.
Pada umumnya individu-individu cenderung menerima dan mempercayai apa yang dikatakan budaya mereka. Hal ini dapat dipahami, karena manusia yang hidup tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh keluarga dan masyarakat dimana kita dibesarkan dan tinggal. Tentunya terlepasdari bagaimana validatas obyektif masukan dan penanaman budaya ini pada diri kita. Pada umumnya individu akan mengabaikan atau menolak apa yang bertentangan “kebenaran” kultural atau bertentangan dengan kepercayan-kepercayaan yang diyakininya.
Budaya adalah gaya hidup unik suatu kelompok manusia tertentu (Dedi Mulyana,2001). Budaya merupakan pengetahuan yang dapat dikomunikasikan, sifat-sifat perilaku dipelajari yang juga ada pada anggota-anggota dalam suatu kelompok sosial dan berwujud dalam lembaga-lembaga artefak-artefak mereka. E.B.Taylor, pakar Antropologi menyebutkan budaya sebagai keseluruhan dimensi meliputi
pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh angggota-anggota suatu masyarakat. Dalam hal ini setiap kelompok budaya menghasilkan jawaban-jawaban khususnya sendiri terhadap tantangan-tantangan hidup seperti kelahiran, pertumbuhan, hubungan-hubungan sosial, dan bahkan kematian.
Sebagaimana telah kita ketahui bahwa budaya memberikan identitas kepada sekelompok orang terhadap karakteristik kulturnya. Beberapa aspek budaya tampak jelas dalam perilaku manusia, namun ada pula aspek lainnya tersembunyi. Sebagian dari aspek-aspek budaya ini eksplisit dalam adat dan pengetahuan masyarakat, dan mungkin berwujud dalam hukum adat, tradisi-tradisi yang dipercayai oleh kelompok masyarakatnya.
Di antara sekian banyak definisi budaya, ada definisi yang menyebutkan budaya sebagai rancangan-rancangan yang tercipta secara historis untuk hidup untuk hidup yang bisa rasional, irasional dan nonrasional. Perilaku rasional dalam suatu budaya didasarkan atas apa yang dianggap kelompok masuk akal untuk mencapai tujuan-tujunannya. Perilaku irasional menyimpang dari norma-norma yang diterima suatu masyarakat dan mungkin bersumber dari frustasi seseorang dalam usaha memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Perilaku irasional akan dilakukan orang tanpa disertai logika dan kemungkinanbesar sebagai suatu respons emosional. Perilaku nonrasional tidak berdasarkan logika, tidak juga bertentangan dengan ekspetasi-ekspetasi yang masuk akal. Banyak perilaku termasuk ke dalam kedua jenis ini. Kita tidak menyadari mengapa kita melakukan perilaku itu,mengapa kita mempercayai yang kita lakukan, atau bahwa mungkin berpra-sangka menurut pandangan orang-orang di luar kelompok budaya kita.
Manusia menciptakan budaya tidak hanya sebagai suatu mekanisme adaptif terhadap lingkungan biologis dan geofisik mereka tetapi jugasebagai alat untuk memberikan adil dari evolusi sosial kita. Dengan demikian manusia sebagai mahluk individu, akan melekat sifat-sifat bawaan yang dapat disebabkan dari sifat generasi manusia sebelumnya.Dalam perkembangannya lingkungan geofisik dimana kita tinggal dan berada seperti rumah, sekolah, tempat ibadah, tempat kantor, atau tempat lainnya memberikan konteks budaya yang berpengaruh terhadap perilaku kita. Budaya memudahkan kehidupan untuk memecahkan masalah-masalah dengan menerapkan pola-pola hubungan, dan cara-cara memelihara kohesi dan konsensus kelompok. Banyak cara atau pendekatan yang berlainan untuk menganalisis dan mengkategorikan suatu budaya agar budaya tersebut lebih mudah dipahami.
D. Peranan Komunikasi dalam Multikultural
1. Unsur-Unsur Komunikasi
Sebelum kita mengkaji secara mendalam tentang peranan komunikasi dalam multikultural. Ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itukomunikasi? Komunikasi didefinisikan sebagai suatu proses dinamik transaksional yang mempengaruhi perilaku sumber dan penerimanya dengan sengaja menyandi (to code) perilaku mereka untuk meng-hasilkan pesan yang mereka salurkan lewat saluran (channel) guna merangsang atau memperoleh sikap atau perilaku tertentu. (Richard E.Porter, 2001). Komunikasi akan lengkap apabila peneri-ma pesan memberikan makna kepadanya dan terpangaruh olehnya. Dalam transaksi ini harus dimasukkan semua rangsangan sadar tak sadar, sengaja-tak sengaja, verbal-nonverbal dan kontekstual yang berperan sebagai isyarat-isyarat kepada sumber dan penerima tentang kualitas dan kredibilitas pesan.
Definisi ini memungkinkan kita mengidentifikasi delapan unsur khususkomunikasi dalam konteks yang sengaja/direncanakan. Pertama, sumber (source) yakni orang yang mempunyai suatu kebutuhan untuk berkomunikasi Kebutuhan ini mungkin berkisar dari kebutuhan sosial untuk diakui sebagai individu hingga kebutuhan berbagai informasi dengan orang lain atau mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang lainnya. Keinginan sumber untuk berkomunikasi adalah keinginan untuk berbagi internal state dengan dengan orang lain dengan derajat kesengajaan yang berbeda-beda untuk mempengaruhipengatahuan, sikap dan perilaku orang lain tersebut.
Kita tidak dapat berbagi perasaan dan pikiran tersebut secara langsung. Kita harus menggunakan lambang-lambang untuk menyampaikan perasaan dan pikiran itu. Hal ini membawa kita kepada unsur kedua penyandi (encoding). Encoding merupakan suatu kegiatan in-ternal seseorang untuk memilih dan merancang perilaku verbal dan non-verbalnya yang sesuai dengan aturan-aturan tata bahasa dan sistaksi guna menciptakan suatu pesan.
Hasil dari perilaku menyandi adalah suatu pesan (message). Suatu operan terdiri dari lanbang-lambang verbal dan atau nonverbal yang mewakili perasaan dan pikiran sumber pada saat dan tempat tertentu. Meskipun encoding merupakan suatu kegiatan internal yang menghasil-kan suatu pesan, pesannya itu sendiri bersifat eksternal bagi sumber, pesan ada;ah apa yang harus sampai dari sumber ke penerima bila sumber ber-maksud mempengaruhi penerima.
Pesan harus menggunakan suatu alat untuk memindahkannya dari suau sumber ke penerima. Unsur komunikasi keempat adalah saluran (channel) yang menjadi penghubung antara sumber dan peneri-ma. Suatusaluran adalah alat fisik yang memindahkan pesan dari sumber ke penerima. Unsur kelima, penerima (receiver) yakni orang yang menerima pesan dan sebagai akibatnya terhubung-kan dengan sumber pesan. Penerima mungkin dikehendaki oleh sumber atau orang lain yangdalam keadaan apapun menerima pesan sekali pesan itu telah memasuki saluran. Unsur komunikasi keenam penyandian balik (decoding) adalah proses internal penerima dan pemberian makna kepada perilaku sumber yang mewakili pikiran dan perasaan sumber.
Sedangkan unsur ketujuh adalah respons penerima (receiver response).Respons ini dapat beraneka ragam seperti keputusan penerima untuk mengabaikan pesan atau tidak berbuat apapun setelah menerima pesan. Terdapat pula respons keputusan penerima untuk segera bertin-dak setelah merima informasi, dan sebagainya bentuk respons seseorang. Selanjunya unsur komunikasi terakhir adalah umpan balik (feedback). Informasi yang tersedia bagi sumber memungkinkan untuk menilai keefektifan komunikasi yang dilakukannya.
Kedelapan unsur yang baru dibahas, perlu untuk diperhatikan dan dipahami bagaimana sebenarnya komunikasi multi-kultural tersebut berlangsung. Dengan kata lain memahami interaksi multi-kultural, terlebih dahulu kita harus memahami komunikasi manusia. Dalam konteks yang lebih luas ini, kita dapat merumuskan budaya sebagai paduan pola-pola yang merefleksikan respons-respons komunikatif terhadap rangsangan dari lingkungan. Pola-pola budaya ini pada gilirannya merefeksikan elemen-elemen yang sama dalam perilaku komunikasi individual yang dilakukan mereka yang lahir dalam budaya tersebut.
2. Pengaruh Komunikasi
Salah satu faktor yang menciptakan kondisi multikultural dapat dipahami masyarakat adalah alat-alat komunikasi yang dirancang dan dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut. Tidak mengherankan bahwa kebangkitan semangat nasionalisme dari potensi multikultural bangsa terjadi ketika teknologi komunikasi berkembang. Melalui alat–alat komunikasi dan perhubungan, sebuah gambaran situasi atau citra tentang sesuatu dengan mudah tersebar secara meluas, melampaui batas-batas geografis, etnis, agama maupun kelas. Hal ini karena dinding partikuralisme lokal baik dalam bahasa, pengalaman, dan gagasan yang selama ini tidak saling bertaut mampu ditembus oleh alat-alat komunikasi modern.
Walaupun nasionalisme adalah sebuah konsep abstrak di mana kelompok-kelompok masyarakat membayangkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama mereka secara lintas suku bangsa, agama, dan kelas di dalam wilayah geografis tertentu. Rasa persatuan tersebut juga menstrukturkan adanya bayangan tentang kesamaaan latar belakang, nasib dan tujuan bersama di dalam sebuah wadah apa yang disebut dengan negara-bangsa.
Dalam hal ini negara sebagai “representatif ekskutif” dari bangsa, melakukan rekayasa untuk mentranfor-masikan identitas dalam loyalitas masya-rakat baik dalam bentuk kelompok-kelompok maupun kelas-kelas, yang sebelumnya terpisah-pisah ke dalam sebuah kesatua baru. Pada tahap perkem-bangan ini, negara dan masyarakat menjadi tak terpisahkan. Eric Hobsbawn (1993) menyebutnya sebagai “the statewas a framework of the citizens collection actions, in so far as thewere officially recognized”. Dalam konteks inilah usaha yang gigih untuk menebarkan gagasan nasionalisme dapat diinternalisasikan ke tengah-tengah masyarakat, walaupun berbeda secara etnik, geografis, agama, dan bahasa. Keampuhan teknologi dan perhubungan dapat mempengaruhi terbentuk semangat nasionalisme ter-sebut.
Kendati Indonesia kini berada dalam masa transisi politik yang memprihatikan, namun dengan memanfaatkan sarana-sarana komunikasi dan perhubungan merupakan potensi besar untuk mem-bangkitkan kembalikesadaran nasionalisme pada bingkai multikultural bangsa di kalanganmasyarakat Indonesia. Ketika digunakan alat komunikasi dan perhu-bungan akan berhadapan dengan kompleksitas kultur pengguna. Hal ini terjadi karena sebagai alat komunikasi masa, teknologi tersebut bukan saja harus berhubungan dengan individu-individu tertentu, melainkan juga berbagai kelompok masyarakat yang berbeda. Karena itu, alat-alat komunikasi pada dasarkan akan tunduk pada struktur nilai, pandangan serta cita-cita pemilik atau pengarah informasi atau pesan yang disalurkan.
Dalam konteks tersebut di atas, penulis dapat menyampaikan suatu hipotesa bahwa untuk sebagian, kelunturan semangat nasionalisme yangberlangsung dewasa ini lebih dipicu oleh sistem gagasan atau konsep-konsep yang melatarbelakangi proses pembuatan dan proses produksi pesan yang disalurkan atau disampaikan melalui teknologi komunikasi.Sebaliknya, juga untuk sebagian, proses pemberdayaan kembali semangat nasionalisme bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi.
E. Revitalisasi Transformasi Sosial Budaya
Pembangunan yang dilaksanakan selama tiga dasawarsa telah memberikanhasil cukup menonjol dalam aspek fisik-material. Namun dominasi pembangunan yang bersifat fisik-material tersebut secara tidak sengaja memarginalkan aspek mental-spiritual, sehingga terjadi disorientasi nilai dalam multikultural bangsa Indonesia. Kenyataan menunjukan bahwa pembangunan yang terpusat pada sektor ekonomi tanpaperkembangan sistem nilai/norma kultur bangsa dan sikap mental yang sinergis, memiliki kecenderungan akan merapuhkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa.
Proses tranformasi ekonomi yang terjadi telah melahirkan budaya materialistik yang justru semakin menumbuh-kembangkan budaya kompetisi liar dan menggerogoti semangat kesetiakawanan sosial, serta kesantunan etis. Hal tersebut dalam kasat mata terlihat dengansemakin maraknya konflik etnis/sosial budaya dan kekerasan kolektif/pengeroyokan dan sebagainya.
Transformasi yang didorong oleh rekayasa sosial dari luar atau dijiwai oleh model-model dari luar memang mungkin terjadi, setidak-tidaknya untuk sementara. Akan tetapi perubahan yang jenis ini akan menuju pada ketergantungan dan bukan ke otonomi, pada ketidakstabilan dan bukan pada ketahanan sosial budaya.
Oleh sebab itu, pendekatan multi-kultural sebagai sebuah konsep rekayasa sosial budaya perlu diintepretasikan kembali secara kritis.Perubahan dalam pembangunan tidak lagi diartikan sebagai proses mengejar dari dunia barat. Modernisasi seharusnya tidak lagi dipertentangan dengan tradisi. Modernisasi yang otentik yang tidak menjurus ke arah lenyapnya identitas diri, harga diri dan kreativitas justru hanya dapat dicapai apabila tradisi diakui sebagai kekuatan dan sumber daya.
Indikasi yang dapat terlihat yakni adanya kesenjangan pranata sosialbudaya lama yang ada dengan pranata sosial budaya baru yang compatible dengan tuntutan prananta ekonomi modern. Telah kita yakini bahwa pendidikan multikultural, salah satu wujud dari tranformasi sosial budaya masyarakat Indonesia. Lemahnya ketahanan nasional (sosial budaya) menuntut kita semua untuk melakukan revitalisasi tranformasi sosial budaya yang berakar dari jati diri unggul yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Di lain pihak, kita menginsafi bahwa interaksi dengan budaya global merupakan keniscayaan yang tidak perlu ditakutkan, justru semestinyadapat dimanfaatkan untuk memperkaya nilai-nilai sosial budaya dengannilai-nilai luhur yang bersifat universal. Hal ini menunjukan sifat keterbukaan yang dimiliki oleh sistem sosial budaya kita belum
sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara tepat dan produktif. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana pendidikan yang berbasis multikultural mampu sebagai katalisator dan tansformasi dari nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa.
F. Reorientasi Pendidikan berbasis Multikultural
UNESCO melalui “the International Commission on Education for the Twenty-first Century” yang dipimpin oleh Jacques Delors menyimpulkanbahwa untuk memasuki abad ke-21, pendidikan kita perlu berangkat dari empat pilar proses pembelajaran; yaitu (1) Learning to know, (2) Learning to do, (3) Learning to be, dan (4) Learning to live together. Penulis berpendapat bahwa penerapan empat pilar proses pembe-lajaran ini pada setiap jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sangat diperlukan bagi terlaksananya fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan nasional dan kaitannya dengan pendidikan multikultural
Penerapan pilar pertama “Learning to know” pada hakekatnya sejalan dengan penerapan paradigma ilmu pengetahuan pada proses pembelajarandi berbagai tingkat pendidikan sejak pendidikan dasar. Melalui penerapan paradigma ini peserta didik akan dapat memahami dan menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomenayang terdapat dalam lingkungannya. Melalui proses pendidikan semacamini sejak SD sampai Perguruan Tinggi diharapkan akan lahir generasi yang memiliki kepercayaan bahwa manusia sebagai kalifah Tuhan di bumi diberi kemampuan untuk mengelola dan mandayagunakan alam bagi kemajuan taraf hidup manusia.
Penerapan pilar kedua “Learning to do” merupakan suatu upaya agar peserta didik menghayati proses belajar dengan melakukan suatu yang bermakna, suatu proses pembelajaran yang dikenal dengan “active learning”. Melalui pendekatan belajar semacam ini seorang peserta didik, misalnya tidak harus selalu mencatat ceramah guru, melainkan ia diminta untuk membaca sendiri bahan yang akan dibahas di kelas dan selanjutnya membahasnya di kelas dengan guru serta kawan-kawannya.
Bentuk lain yang termasuk belajar aktif dapat berupa penugasan untukmembuat ringkasan buku atau artikel yang ditugaskan kepada peserta didik untuk membacanya. Dan banyak bentuk belajar aktif lainnya yangmemungkinkan peserta didik berkesempatan aktif, baik secara intelektual, motorik, maupun emosional. Setiap mata pelajaran dan bahan pelajaran pada dasarnya dapat dijadikan objek belajar dengan pendeka-tan “active learning”.
Model belajar aktif dapat juga, dan seyogyanya, diterapkan di semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan, dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Karena model belajar seperti ini akan memungkinkandapat tercapainya tujuan untuk mengembangkan manusia seutuhnya.
Pelaksanaan pilar ketiga “Learning to be” adalah suatu prinsip pendidikan yang dirancang bagi terjadinya proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik yang mandiri. Rasa kemandirian akan tumbuh dari sikap percaya diri, dan sikap percaya diri akan lahir dari pemahaman dan pengenalan dirinya secara tepat. Atas dasar ini maka proses pembelajaran pertama harus memungkinkan peserta didik mengenal dirinya dengan penuh kebahagiaan. Dan ini sukar diperoleh dalam proses pembelajaran tradisional yang menekan-kan pada hafalan.
Kebahagiaan akan diperoleh melalui belajar aktif dan belajar tuntas.Pendeka-tan melalui penerapan paradigma ilmu pengetahuan, seperti pendekatan menemukan dan pendekatan menyelidik akan memungkinkan peserta didik menemukan kebahagiaan dalam belajar.
Pendekatan belajar aktif yang pada hakekatnya sama dengan pendekatanpertama juga memungkinkan kepada peserta didik untuk menemukan kebaha-giaan dalam belajar yang pada akhirnya dapat menemukan dirinya. Menemukan dan mengenal dirinya merupakan pangkal dari proses anak untuk tidak bergantung pada orang lain, dan hal ini merupakan bentuk belajar yang akan menunjang terbentuknya pribadi yang mandiri sebagaimana kita cita-citakan.
Penerapan pilar “Learning to live together” di dunia internasional dipan-dang bertambah penting karena dalam era globalisasi yang saratdengan muatan teknologi dan perdagangan bebas, dimensi kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh setiap agama sering terlupakan karena tekanannya pada pertambahan nilai secara kebendaan. Karena itu, proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati hubungan antara manusia secara intensif dan terus menerus sangatlah penting. Pertentangan yang dasarnya perbedaan ras, agama, suku, keyakinan politik, dan kepentingan ekonomi yang masih sering terjadi, perlu dihindarkan. Karena itu, pendidikan nilai kemanusiaan, moral, dan agama yang melandasi hubungan antar manusia perlu diintensifkan.
Keempat pilar terseut di atas, secara potensial dapat dintegrasikan dengan pendidikan yang berbasis multikultural. Sehingga budaya damai“culture of peace” akan dapat terwujud berdasarkan multukultural bangsa Indonesia. Dalam hal ini keempat pilar proses pembelajaran
bagi dapat terlaksananya fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan nasional, berbagai strategi perlu dikembangkan.
Pertama, perlu dikembangkan suatu sistem kurikulum yang memungkinkandapat berlangsungnya proses pembelajaran yang secara epistomologis, psikologis, dan sosial/moral relevan. Salah satu konsekuensi dari penerapan ini adalah pembaharuan kurikulum dengan mengutamakan materi yang esensial dan sistem evaluasi yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional.
Kedua, perlu peningkatan kualitas profesional tenaga kependidikan melalui penyempurnaan sistem pendidikan pra-jabatan dan dalam jabatan guru, serta pembinaan guru untuk meningkatkan kewibawaan guru dan tenaga kependi-dikan lainnya.
Ketiga, perlu pengembangan sistem pengelolaan pendidikan dengan mene-gakkan sekolah/lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai-nilai yang sesuai dengan tuntutan masyarakat maju yang berdasarkan Pancasila.
Keempat, perlu mengembangkan sistem pendidikan tinggi, terutama Universitas/Institut yang benar-benar mampu melaksanakan doktrin TriDharma Perguruan Tinggi sehingga Perguruan Tinggi dapat menjadi agenpembangunan masyarakat daerah pada khususnya, dan negara bangsa padaumumnya.
Kelima, perlu menyamakan persepsi masyarakat, terutama orang tua dantokoh masyarakat serta pemimpin formal, tentang perlunya memberikan dukungan bagi dapat terlaksananya fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan nasional.
Pendidikan mutikultural menurut Bank (2000) pada hakekatnya bertujuan untuk mengadakan perubahan pada sistem pendidikan dan pembelajaran. Sehingga siswa yang berasal dari latar belakang kelas sosial, suku bangsa/etnik, gender dan agama yang berbeda-beda dapat memperoleh pendidikan yang sama
Sejumlah fenomena yang terjadi di Indonesia memperlihatkan betapa pentingnya suatu strategi pendidikan berbasis multikultural untuk bangsa yang besar dan majemuk seperti Indonesia. Ancaman disintegrasi bangsa, arogansi kesukuan, terpinggirkannya daerah-daerah konflik antar etnis dan agama, masalah transmigrasi dan permukiman, fenomena korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), dan sejumlah fenomena lainnya, merupakan akibat dari tiadanya atau kelirunya strategi pendidikan dan kebudayaan, khususnya pendidikan berbasis multi-kultural.
Beberapa kontroversi dan kerancuan di dalam perkembangan kebudayaan Indonesia telah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Kita ingin mengem-bangan masyarakat dan kebudayaan yang memiliki identitas, tetapi sementara itu dikebangkan pula sistem dan proses sentralisasiyang mengabaikan daerah-daerah sebagai sumber identitas dan nilai bagi bangsa Indonesia.
Kebudayaan nasional hanya menjadi-kan puncak-puncak kebudayaan daerah. Paradigma dan konsep tentang kebudayaan nasional itu telah meminggirkan potensi sektor budaya yang ada (hukum, pemerintahan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, bahasa, kesenian, moral dan sebagainya) dari berbagai etnis di Nusantara. Paradigma negara kesatuan menimbulkan konsekuensi agar Indonesia juga haruis memilikisuatu kebudayaan, yakni kebudayaan nasional. Paradigma itu mengingkari kenyataan yang adanya pluraisme budaya dilihat sebagai sesuatu yang berbahaya.
Adanya suatu strategi pendidikan berbasis multikultural akan menjagaagar manusia selalu merupakan faktor sentral dalam pembangunan. Manusia merupakan subyek dan tujuan dalam setiap langkah dan upaya perubahan. Dalam hubungan dengan teknologi, misalnya manusia seyogyanya menjadi subyek bukan mangsa, dan seyogyanya pula teknologi bisa lebih memanusiawikan dan membahagiakan manusia Indonesia.
Tantangan budaya yang dimiliki oleh Indonesia sangatlah berat. SebabIndone-sia adalah masyarakat majemuk, terdiri dari sejumlah etnik dan dalam keberagaman budaya. Masyarakat yang majemuk dan beragam itulah yang akan membentuk masyarakat Indonesia, sekali-gus sebagai cikal/tunas bagi tumbuhnya kebudayaan Indonesia. Dalam konteks ini masyarakat dan kebudayaan yang baru itu bukanlah hasil penjumlahan dari masyarakat dan kebudayaan etnis yang ada. Kehadiran kebudayaan global (budaya antar bangsa) membuat nilai-nilai budaya etnis akan terasa dalam budaya etnis yang kuat dan lentur akan memberikan kontribusi yang penting dalam proses pembentukan kebudayaan baru.
Proses pembentukan kebudayaan Indonesia berlangsung tidak melalui proses yang sentralistis. Beberapa sentra dan kantung-kantung kebudayaan harus ditumbuhkembangkan, guna memungkin-kan nilai-nilai budaya etnis dapat dipadukan dan menemui titik singgung dengan nilai-nilai budaya global. Nilai-nilai budaya yang demikian akan membentuk sistem budaya dalam meng-hadapi tantangan kebudayaan di masa depan. Oleh karena itu implikasinya harus dapat terlihat denganjelas dalam sistem pendidikan yang berbasis multi-kultural.
Di sisi lain, nilai budaya itu harus memiliki suatu identitas (sesuatu yang lebih berakar di masyarakatnya), dan pihak lain nilai itu menjadi universal. Proses desentralisasi kebudayaan akan memberikan tempat kepada sentra an kantung-kantung kebudayaan yang tersebar di berbagai daerah di Nusantara. Keadaan ini akan menumbuhkan kreativi-tas bangsa, dan juga memiliki arti penting bagiketahanan budaya dari suatu bangsa yang majemuk.
Paradigma pendidikan berbasis multi-kultural tidak saja mengandaikanhadir-nya anekaragam elemen sosial budaya, tetapi juga proses amalgaminasi atau peleburan antara elemen yang satu dengan elemen lain ke dalam sebuah bejana sosial budaya yang bersifat fluid dan melting (Masdar Hilmy, 2002). Proses amalgimasi ini bukan dalam pengertian penciptaan identitas tunggal melalui penyeragaman yang representatif, tetapi kerelaan saling melebur tanpa menghilangkan identitas-identitas lokal.
Pendidikan berbasis multikultural, belum mampu menyangga multikul-turalitas kebangsaan yang genuine dan otentik. Proses pendidikan yang terse-lenggara melalui jalur sekolah, luar sekolah (masyarakat)ataupun keluarga, belum dapat menjawab epistomologi multikultural. Ketidakterpaduan antara kebijakan, konsep dan implementasi dalam pendidikan yang berbasis multi-kultural, dapat mengakibatkan tersendat-nya perkembangan budaya nasional. Hal ini pun disadari oleh para pakar di bidang antropologi, sosiologi, demografi, dan pakar lainnya sulitnya untuk mengangkat berbagai budaya lokal untuk mewujudkan budaya nasional.
Proses reformasi yang terjadi di Indonesia, dimana terjadi transisi pada sistem ketatanegaraan yang dulu bero-rientasi pada sentralistikmenjadi desentralisasi akan membawa berbagai konsekuensi. Penulis berkeyakinan bahwa salah satu konsekuensinya adalah kebijakan dan implementasi dari sistem pendidikan nasional perlu untuk dikaji ulang, khususnya perhatian yang serius tentang pendidikan yang berbasis multikultural.
G. Revitalisasi Kurikulum
Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, maka kedudukan kurikulum menjadi sangat strategis dan penting. Pada dasarnya pembahasan pendidikan mutikultural difokuskanpada tiga hal yakni pertama, pendidikan multikultural sebagai studi tentang etnisitas yaitu penelaahan terhadap berbagai kelompok etnis/budaya, keunikan masing-masing etnik serta kontribusinyanya terhadap kebudayaan nasional. Kedua pendidikan multikultural mempelajari dampak dari ketidakadilan. Dalam hal ini menggunakan
pendekatan historis dan analisis hubungan sosiologis antar kelompok.Sedangkan penekannya pada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan praktek-praktek stereotipe, bias, dan deskriminasi terhadap potensi dalam masyarakat.
Ketiga, multikultural sebagai suatu proses pembelajaran. Implikasi dari pendidikan multikultural yang ketiga ini mencakup hasil serta proses instruksionalnya. Termasuk di dalamnya pemahaman para pendidik terhadap komponen utamam dalam kurikulum yakni; tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi.
Pendidikan multikultural memerlukan kurikulum yang bersifat akomodatif dan komprehensif, artinya selain dapat memenuhi kebutuhantentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap namun juga memenuhi terwujudkan kerukunan dalam multikultural bangsa. Dengan harapan agar terwujud proses pembelajaran yang menyenangkan dan kondusif, walaupun dari berbagai ragam budaya.
Dalam rangka untuk mengaktualisasikan pendidikan berbasis multi-kultural, haruslah memperhatikan berbagai dimensi yang saling berelasi satu sama lain. Menurut Banks (2000) dimensi-dimensi tersebut meliputi yakni;
1. Integrasi Materi
Dalam pendidikan multikultural pada guru harus mampu memberikan contoh-contoh yang berasal dari berbagai budaya untuk menjelaskan materi pembelajaran. Dengan demikian guru perlu untuk memiliki kemampuan mengintegrasikan materi ke dalam perspektif budaya pesertadidik. Integrasi materi ini dimaksudkan pula adanya saling keterkaitan materi pembelajaran dengan konteks sosial budaya pesertadidik, sehingga belajar menjadi bermakna bagi mereka.
2. Proses Konstruksi Pengetahuan
Guru berperan untuk membantu para peserta didik membangun pengetahuan dari perspektif budaya yang berbeda. Dengan harapan akanterbentuk suatu pengetahuan yang universal, artinya dapat diterima oleh semua peserta didik.
3. Pengurangan prasangka Buruk/Negatif
Pendidikan dengan latar belakang budaya yang berbeda seringkali menimbulkan prasangka buruk/negatif di antara para peserta didik, bahkan dapat mengarahkan para pertentangan atau konfilk. Dalam
kontek ini guru dapat berperan untuk membantu peserta didik bersikappositif terhadap kelompok suku bangsa, ras, agama, dan budaya yang berbeda. Dengan harapan sikap prasangka buruk sebagai implikasi dariperbedaan tersebut, dapat dikurangi bahkan dihilangkan sama sekali.
4. Kesamaan Pedagogis
Kesamaan perspektif pedagogis para guru terhadap pendidikan multikultural adalah kunci utaa bagi guru untuk memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Selain itu kesaman pedagogis iniakan dapat berlangsung dengan baik apabila masing-masing guru mau menganalisis semua aspek pemeblajaran yang dilakukannya, dan melihatnya kembali dalam perspektif keragamaan budaya. Dengan demikian para guru dapat mengoptimalkan prestasi akademik siswanya yang datang dari latar belakang budaya yang berbeda.
5. Pemberdayaan Budaya dan Sekolah
Keberhasilan pendidikan multikul-tural harus dilihat dari kemampuannya memberdayakan perbedaan yang ada (kelas sosial, kelompok gender, suku bangsa, ras/etnik, agama dan sebagainya). Olehkarena itu uapaya membantu pada guru dan staf memahami sikap dan nilai-nilai demokrasi adalah hal yang sangat penting. Di samping itumembangun interaksi antara para staf dan peserta didik yang berbeda ras/etnik dan sebagainya, akan meningkatkan kemampuan sekolah mengelola keragaman budaya yang ada. Dengan kata lain sekolah harus mampu mengelola perbedaan yang ada menjadi kekuatan mencapai tujuan pembelajaran.
Dalam pengembangan dan imple-mentasi kurikulum dikaitkan dengan kenyataan multikultural ini sekurang-kurangnya ada tiga langkah yangpatut mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka penciptaan pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Pertama, pengidentifikasian faktor sosial dan kultural yang berkontribusi positif pada perbedaan individu peserta didik. Kedua, perancang fan pengorganisasian cakupan kurikulum dan langkah pengajran dalam menjangkau tujuan pemahaman diri dan realisasi diri secara sosial. Ketiga, penciptaan suasana yang mampu mengembangkan keterampilan memecahklan masalah lahir bathin yang diperlukan oleh peserta didik dalam mengarungi samudera kehidupan multikultural.
Di sisi lain stereotipe budaya berskala luas yang dipandang negatif patut mendapatkan perhatian khusus. Dalam konteks ini, Koentjaraningrat mengidentifikasi sifat mentalitas yang negatif seperti meremehkan mutu, suka menerabas, tidak percaya diri, tidakj
berdisiplin, dan mengabaikan tanggung jawab. Sedangkan Mochtar Lubis(1999) memberikan sifat-sifat seprti hipokrit, segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, feodalistik, percaya pada takhayul, artistik, dan kurang kuat mempertahankan keyakinan. Lepas dari benar atau tidaknya identifikasi itu, dalam proses multikultural, sifat-sifat dasar itu sering dijadikan stereotipe untuk kelompok etnis tertentu oleh kelompok etnis lainnya. Pengidentifikasian streotipe ini patut dilakukan secara sadar dalam pengembangan dan implementasi kurikulum.
Stereotipe berskala kecil patut diamati untuk selanjutnya dibenahi atau dibina agar harmonis dan konstruktif dalam konteks pembinaan bangsa secara keseluruhan. Nilai-nilai keyakinan keagamaan, misalnyasering mewarnai gaya dan corak kehidupan keluarga dan kelompok kecildalam masyarakat. Perbedaan individual peserta didik banyak ditentukan oleh strerotipe budaya yang berskala kecil ini patut memperoleh perhatian khusus dari para pendidik dan siapa pun yang terlibat dalam usaha-usaha pendidikan.
Upaya revitalisasi kurikulum dalam mengakomodasi multikultural, hendak-nya mengidentifikasi yakni; 1) faktor sosial budaya yang kemungkinan dapat menjadikan perbedaan individual peserta didik sebagai faktor-faktor yang konstruktif ; 2) mengidentifikasi niali-nilai apa yang sepatutnya diajarkan secara eksplisit maupun implisit. Selain itu penyusunan kurikulum harus mampu mengakomodir terhadap perbedaan kultural individu peserta didik. Dengan harapan agar peserta didik dengan latar budaya yang berbeda dapat memperkayakultural yang dimilikinya dari proses interaksi dengan perserta didik lainnya.
Pada akhirnya ragam kultur justru akan memberikan peluang bagi keutuhan dalam membentuk budaya bangsa. Dalam kontek ini membina kebhinekaan budaya berarti memahami dan menghargai perbedaan yang ada di warga masyarakat nbangsa ini. Bila kita memandang kebhinekaaan budaya sebagai kualitas dasar budaya kita, kebhinekaan budaya itu harus menjadi bagian integral proses pendidikan pada semua jenis, jenjang, serta jalur pendidikan.
H. Penutup
Multikultural sebagai sesuatu yang telah terjadi sejak lama bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya mengandung benih-benih sikap primordial, tetapi apabila multikultural dikelola dengan tepat dan benar bukanlah kendala dalam proses pembentukan masyarakat madani. Bahkan keadaan tersebut sebenarnya merupakan
kekayaan bangsa yang potensial. Oleh karena itu, persoalannya di masa depan tidak terletak pada kondisi primordial-pluralistik sendiri tetapi pada para pengelola bangsa ini bersama seluruh rakyatnya. Dengan demikian akan terbentuk “masyarakat madani” sebagai masyarakat warga sadar politik yang bebas berpartisipasi, berkomitmen, bertindak secara bijaksana untuk membangun negara.
Sejarah peradaban bangsa-bangsa besar adalah sejarah mengelola multikultural yang dimilikinya dengan kebijakan dan implementasi yang tepat sesuai karakter bangsanya. Sebaliknya sejarah kehancuran bangsa-bangsa yang besar adalah sejarah kegagalan dalam mengelola multikulturalitas kebangsaan-nya. Semakin tinggi tingkat heterogenitas sebuah bangsa, semakin tinggi pula tingkat tantangan yang dimiliki. Meski demikian tingkat keberhasilan menjadi bangsa besar semakin terbuka seiring keberhasilannya mengatasi problem-problem yang muncul dari heterogenitas itu.
Proses reformasi yang telah berlangsung pada hakekatnya menuntut pula kontribusi pendidikan dalam menghasilkan manusia yang berkualitas, berbudi luhur dan menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya (mencintai kultur bangsanya). Oleh karena itu kebijakan dan implementasi pendidikan yang berbasis multikultural sebagai faktor penting yang perlu diperhatikan dalam membangun bangsa dan negara Indonesia di masa kini dan yang akan datang.
Pemahaman dan akselarasi pendidikan yang berbasis multikultural menjadi sangat penting untuk dihayati bagi generasi muda. Terutama untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman dari awalmengenai multikultural setidaknya akan mempengaruhi perkembangan generasi muda Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu proses pendidikan yang berbasis multikultural, tidak saja berlangsung di sekolah namun juga luar sekolah (masyarakat) dan keluarga. Dengan demikian diharapkan akan terjadi kerukunan antara suku/etnik yang berbeda-beda dan secara bersama-sama membangun bangsa dan negara yang tercinta Indonesia.
Daftar Pustaka
Banks, James A, And Bank, Cherry A. (1997), Multicultural Education,Boston: Alan and Bacon.
Deddy Mulyasa dan Jalaluddin Rakhmat, (2001). Komunikasi Antar Budaya, Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya, Bandung Penerbit Rosda.
Renwich George W., (2000), Evaluation: Multicultural Education; Across Culture training Aprroach, Maine:Intercultural Press Inc.
Eric Hobsbawn, (1993), The Invention of Tradition, Cambridge: Camto.
Fachry Ali, (2002), Budaya, Nasionalisme, dan Komunikasi, Makalah disampaikan dalam Seminar Tranformasi Sosial Budaya
Hass, Glen, (1977) Curriculum Planning, A New Approach, University of Florida.
Hidayat, Zulyani, (1997). Eksklopedi Suku Bangsa Indonesia, Jakarta,LP3ES.
Koentjaraningrat, (1993). Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
Kuntowijoyo (1998) “Transformasi Kultural Daerah ke Nasional”, dalamIkhnaul Amal & Armaidy Armawi, Nasionalisme dan Ketahanan Nasional, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
Masdar Hilm Hilm, (2002), Pendidikan Berbasis Multikultural, dalam surat kabar Kompas, Kamis 14 Novemer 2002
Nasikun, (2000), Sistem Sosial Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada
Putu Wjaya, (2002), Transformasi Budaya, Makalah disampaikan dalam Seminar Tranformasi Sosial Budaya.
Sumarno dan Suwawarsih Madya, (2002), Studi Kebijakan Pendidikan Perdamaian: Perspektif Multikul-tural dan Pendidikan Sepanjang Hayat, Makalah disampaikan dalam Widyakarya Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda di Jakarta 15 Agustus 2002.
Oleh: Muktiono Waspodo Alumnus PPS UNJ, Pemerhati Pendidikan, Kabag Umum PPPPTK Penjas danBK