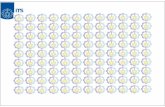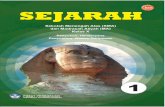Metode dan Ilmu Bantu Sejarah
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Metode dan Ilmu Bantu Sejarah
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam mempelajari sebuah disiplin ilmu, kita harus
mengetahui bagaimana metode atau cara-cara yang ada
dalam mempelajari sebuah disiplin ilmu tersebut. Dalam
belajar sebuah disiplin ilmu kita juga harus mengetahui
bagaimana atau apa saja ilmu bantu yang ada dari
disiplin ilmu tersebut, karena sebuah disiplin ilmu
pasti memerlukan ilmu-ilmu bantu. Selain kedua hal
tersebut, kita juga harus mengetahui bagaimana hubungan
disiplin ilmu tersebut dengan disiplin ilmu-ilmu yang
lain.
Semua uraian di atas juga terdapat dalam disiplin
ilmu sejarah. Dalam mempelajari disiplin ilmu sejarah
kita tidak lepas dari metode-metode atau cara-cara,
apalagi sejarah adalah sebuah ilmu tentang kehidupan di
masa lampau, agar penjelasan tentang masa lampau
tersebut dapat dimengerti atau dipahami tentunya dalam
membuat sebuah pernyataan sejarah seorang sejarawan
harus memiliki metode-metode. Dalam upaya penjelasan
sejarah para sejarawan juga tidak lepas dari bantuan
ilmu-ilmu yang lain, karena dalam pengumpulan data-data
untuk penjelasan sejarah seorang sejarawan harus
menggunakan ilmu bantu seperti, ilmu tentang gejala
alam, ilmu tentang masyarakat, dan yang lainnya. Selain
1
itu, sejarah tentunya juga memiliki hubungan dengan
ilmu yang lainnya. Walaupun sejarah adalah ilmu yang
mandiri, tapi sejarah juga memiliki hubungan dengan
ilmu yang lainnya.
1.2. Rumusan Masalah
1. Apa metode-metode dalam ilmu sejarah ?
2. Apa ilmu bantu dalam ilmu sejarah ?
3. Bagaimana hubungan ilmu sejarah dengan ilmu yang
lain ?
1.3. Tujuan
1. Menjelaskan apa saja metode-metode dalam ilmu
sejarah.
2. Menjelaskan ilmu-ilmu bantu dalam ilmu sejarah.
3. Menjelaskan bagaimana hubungan ilmu sejarah dengan
ilmu-ilmu yang lain.
2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Metode Dan Ilmu Bantu Sejarah
Dalam metodologi riset, kita sering mendengar
metode historis dengan langkah-langkah, define the problems
or question to be investigated; searh for sources of historical fact;
summarize and evalute the historical source; and present the pertinent
3
facts within an interpretative framework (Edson, 1986: 20)
‘menggambarkan permasalahan atau pertanyaan untuk
diselidiki; mencari sumber tentang fakta historis;
meringkas dan mengevaluasi sumber-sumber historis; dan
menyajikan fakta-fakta yang bersangkutan dalam suatu
kerangka interpretatif’. Sepintas, tampaknya begitu
mudah untuk mengadakan penelitian historis tersebut,
namun dalam praktiknya tidak saemudah yang kita
bayangkan. Secara sederhana, Ismaun (1993: 125-123)
mengemukakan bahwa dalam metode sejarah meliputi
meliputi (1) heuristik (pengumpulan sumber-sumber); (2)
kritik atau analisis sumber (eksternal dan internal);
(3) interpretasi; (4) historiografi (peulisan sejarah).
Di sini jelas bahwa untuk melakukan penelitian dan
penulisan sejarah dituntut keterampilan-keterampilan
khusus tertentu.
Namun, seorang sejarawan ideal, baik itu sejarawan
profesional maupun sebagai sejarawan pendidik (guru
sejarah) perlu memiliki latar belakang beberapa
kemampuan yang dipersyaratkan. Sjamsudin (1996: 68-69)
merinci ada tujuh kriteria yang dipersyaratkan sebagai
sejarawan, sebagai berikut.
1. Kemampuan praktis mengartikulasi dan mengekspresikan
pengetahuannya secara menarik, baik secara tertulis
maupun lisan.
2. Kecakapan membaca dan/atau berbicara dalam satu atau
dua bahasa asing atau daerah.
4
3. Menguasai satu atau lebih disiplin kedua, terutama
ilmu-ilmu sosial lainya, seperti antropologi,
sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, atau ilmu-
ilmu kemanusian (humaniora), seperti filsafat, seni
atau sastra, bahkan kalau mungkin relevan juga yang
berhubungan dengan ilmu-ilmu alam.
4. Kelengkapan dalam penggunaan pemahaman (insight)
psikologi, kemampaun imajinasi, dan empati.
5. Kemampuan membedakan antara profesi sejarah dan
sekedar hobi antikurian, yaitu pengumpulan benda-
benda antik.
6. Pendidikan yang luas (broad culture) selama hidup
sejak dari masa kecil.
7. Dedikasi pada profesi dan integrasi pribadi, baik
sebagai sejarawan peneliti maupun sebagai sejarawan
pendidik.
Selanjutnya, dikemukakan pula oleh Gray (1964: 9)
bahwa seorang sejarawan minimal memiliki enam tahap
dalam penelitian sejarah.
1. Memilih suatu topik yang sesuai.
2. Mengusut semua evidensi atau bukti yang relevan
dengan topik.
3. Membuat catatan-catatan penting dan relevan dengan
topik yang ditemukan ketika penelitian dilakukan.
4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah
dikumpulkan atau melakukan kritik sumber secara
eksternal dan internal.
5
5. Mengusut hasil-hasil penelitian dengan mengumpulkan
catatan fakta-fakta secara sistematis.
6. Menyajikan dalam suatu cara yang menarik serta
mengomunikasikannya kepada pembaca dengan menarik
pula.
Sedangkan sebagai ilmu bantu dalam penelitian,
sejarah terdiri atas hal-hal berikut.
1. Paleontologi, yaitu ilmu tentang bentuk-bentuk
kehidupan purba pernah ada di muka bumi, terutama
fosil-fosil.
2. Arkeologi, yaitu kajian ilmiah mengenai hasil
kebudayaan, baik dalam priode prasejarah maupun
priode sejarah yang ditemukan melalui ekskavasi-
ekskavasi di situs-situs arkeolog.
3. Paleontropologi, yaitu ilmu tentang manusia-manusia
purba atau antropologi ragawi.
4. Paleografi, yaitu kajian tentang tulisaan-tulisan
kuno, termasuk ilmu membaca dan penentuan
waktu/tanggal/tahun.
5. Epigrafi, yaitu pengetahuan tentang cara membaca,
menentukan waktu, serta menganalisis tulisan kuno
pada benda-benda yang dapat bertahan lama (batu,
logam, dan sebagainya)
6. Ikonografi, yaitu arca-arca atau patung-patung kuno
sejak zaman prasejarah maupun sejarah.
7. Numisnatik, yaitu tentang ilmu mata uang, asal usul,
teknik pembuatan, dan mitologi.
6
8. Ilmu keramik, kajian tentang barang-barang untuk
tembikar dan porselin.
9. Genealogi, yaitu pengetahuan tentang asal usul nenek
moyang asal mula keluarga seseorang maupun beberapa
orang.
10. Filologi, yaitu ilmu tentang naskah-naskah kuno.
11. Bahasa, yaitu pengusaan tentang beberapa bahasa,
baik bahasa asing maupun bahsa daerah yang
diperlukan dalam penelitian sejarah.
12. Statistik, adalah sebagai presentasi analisis dan
interpretasi angka-angka terutama dalam
quantohistory atau cliometry
13. Etnografi, merupakan kajian bagian antropologi
tentang deskripsi dan analisis kebudayaan suatu
masyarakat tertentu.
2.2. Hubungan Ilmu Sejarah Dengan Ilmu-Ilmu Sosial
Lainya
1. Hubungan Sejarah dengan Sosiologi
Hal ini lebih tampak lagi dengan cepatnya
perubahan sosial jelas menarik perhatian bukan saja
sejarawan, tetapi juga sosiologiwan. Sebab para
sosiologiwan yang menganalisis berbagai persyaratan
pembangunan pertanian dan industri di negara-negara
yang disebut negara berkembang memperoleh kesan yang
mereka kaji adalah tentang perubahan dari waktu ke
waktu, dengan kata lain sejarah. Sebagian di antaranya,
seperti sosiologiwan Amerika Serikat Imanuel
7
Wallerstein yang begitu tergoda untuk memperluas
penyelidikannay hingga jauh ke masa silam, khususnya
tentang Ekonomi Dunia Kapitalis (Wallerstein, 1996:
537).
Terdapat tiga tokoh besar ahli sosiologiwan yang
sangat mengagumi sejarah, yaitu Pareto, Durkheim, dan
Weber, mereka menguasai sejarah dengan amat baik. Buku
Vilfredo Pareto, Treatise on General Sociology (1916)
banyak berbicara tentang sejarah Athena, Sparta, Romawi
klasik dengan mengambil contoh-contoh sejarah Italia
Abad Pertengahan. Sementara itu, Emile Durkheim yang
dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri sosiologi
sebagai ilmu, ia melakukan pembedaan antara sosiologi,
sejarah, filsafat, dan psikologi. Dia merasa perlu
belajar sejarah kepada Fustel de Coulanges. Bahkan,
salah satu bukunya itu dipersembahkan untuk Coulanges,
ia pun menulis monograf sejarah pendidikan Prancis.
Selain itu, ia menjadikan buku sejarah sebagai salah
satu sajian jurnal Anne Sociologique, dengan syarat
pembahasan buku itu bukan hal-hal yang superfisial
seperti umumnya buku-buku sejarah peristiwa (Lukes,
1973; Burke, 2001). Sedangkan tentang Max Weber,
sosiologi yang memiliki wawasan luas tentang sejarah,
sebelum melakukan studi untuk bukunya The Protestan
Ethic and the Spirit of Capitalism (1904-1905),
sebelumnya ia telah menulis tentang perniagaan abad
pertengahan serta sejarah pertanian zaman Romawi Kuno.
8
Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali karya
sosiologiwan diterbitkan yang berupa studi sosiologis
mengenai gejala sosial atau sociofact di masa lampau,
seperti Pemberontakan Petani karya Tilly, Perubahan
masa Revolusi Industri di Inggris oleh Smelzer, dan
Asal Mula Sistem Totaliter dan Demokrasi oleh
Barrington Moore, yang kesemuannya itu disebut sebagai
historical sociology ‘sejarah sosiologis’ (Kartodirdjo,
1992: 144). Adapun karakteristik dari historical
sosiology tersebut bahwa studi sosiologis tentang suatu
kejadian atau gejala di masa lampau yang dilakukan oleh
para sosiologiwan.
Di satu pihak, sekarang ini pun sedang terjadi apa
yang disebut sociological history (sejarah sosiologis)
yang menunjuk kepada sejarah ang disusun oleh sejarawan
dengan pendekatan sosiologis. Timbul pertanyaan,
mengapa perkembangan ilmu sejarah atau studi sejarah
kritis sejak akhir Perang Dunia II menunjukkan
kecenderungan kuat untuk mempergunakan pendekatan ilmu
sosial?
Untuk menjawab itu, memang akhir-akhir ini
sedang terjadi a[a yang disebut sebagai gejala
Rapprochement atau proses saling mendekat antara ilmu
sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Metode kritis ini
berkembang pesat sejak diciptakan oleh Mabilon sehingga
terjadi inovasi-inovasi yang sangat penting dalam
sejarah,yang mana dapat menyelamatkan sejarah dari
9
“kemacetan” (Kartodirdjo:1992: 120). Sebab jika
dipandang dari titik sejarah konvensional, perubahan
metodologi tersebut sangat revolusioner dengan
meninggalkan model penulisan sejarah naratif. Dikatakan
revolusioner karena ilmu sejarah lebih bergeser ke ilmu
sosial. Perubahan paradigma ini beranggapan bahwa dapat
diingkari tanpa bantuan budaya, dan geografi, sukar
dianalisis dan dipahami proses-prosesnya. Kombinasi
antar berbagai perspektif akan mampu
mengekstrapolasikan interdepensi antara berbagai aspek
kehidupan. Dalam hal ini, sejarawan tidak langsung
berurusan dengan kausalitas, tetapi lebih banyak
kondisi-kondisi dalam berbagai dimensinya.
2. Hubungan Sejarah dengan Antropologi
Hubungan ini dapat dilihat karena kedua disiplin
ini memiliki persamaan yang menempatkan manusia sebagai
subjek dan objek kajiannya, lazimnya mencakup berbagai
dimensi kehidupan. Dengan demikian, di samping memiliki
titik perbedaan, kedua disiplin itu pun memiliki
persamaan. Bila sejarah membatasi diri pada
penggambaran suatu peristiwa sebagai proses di masa
lampau dalam bentuk cerita secara einmalig ‘sekali
terjadi’, hal ini tidak termasuk bidang kajian
antropologi. Namun, jika suatu penggambaran sejarah
menampilkan suatu masyarakat di masa lampau dengan
berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik,
religi, dan keseniannya maka gambaran tersebut mencakup
10
unsur-unsur kebudayaan masyarakat. Dalam hal itu ada
persamaan bahkan tumpang-tindih antara sejarah dan
abtropologi (Kartodirdjo, 1992: 153).
Memang ada persamaan yang menarik jika hal itu
dihubungkan dengan ucapan antropolog terkemuka Evans-
Pritchard. Ia mengemukakan bahwa Antropologi adalah
sejarah. Hal itu dapat dipahami karena dalam studi
antropologi diperlukan pula penjelasan tentang
struktur-struktur sosial yang berupa lembaga-lembaga,
pranata, dan sistem-sistem, yang kesemuanya itu akan
dapat diterangkan secara lebih jelas apabila
diungkapkan bahwa struktur itu adalah produk dari suatu
perkembangan masa lampau. Karena antropologi pun
mempelajari objek yang sama, yaitu tiga jenis fakta
yang terdiri atas artifact, sociofact, dan mentifact,
di mana semuanya adalah produk historis dab hanya dapat
dijelaskan eksistensinya dengan melacak sejarah
perkembangannya (Kartodirdjo,1992:153).
3. Hubungan Antropologi Budaya dengan Sejarah
Hal ini dapat dipahami, mengingat ada dua hal yang
penting. Pertama, makna kebudayaan telah semakin meluas
karena semakin luasnya perhatian para sejarawan,
sosiologiwan, mengkritisi sastra, dan lain-lain.
Perhatian semakin dicurahkan kepada kebudayaan populer,
yakni sikap-sikap dan nilai-nilai masyarakat awam serta
pengungkapannya ke dalam kesenian rakyat, lagu-lagu
11
rakyat, cerita rakyat, festival rakyat, dan lain-lain
(Burke, 1978; Yeo dan Yeo, 1981). Kedua, mengingat
semakin luasnya makna kebudayaan semakin meningkat pula
kecenderungan untuk menganggap kebudayaan sebagai
sesuatu yang aktif, bukan pasif. Kaum strukturalis
tentu telah berusaha mengembalikan keseimbangan itu
yang telah terancam begitu lama, terutama Levi-Strauss,
pada mulanya begitu membanggakan KarL Marx, akhirnya
berpaling kembali kepada Hegel dengan mengatakan bahwa
yang sebenarnya struktur dalam bukanlah tatanan sosial
dan ekonomi, melainkan kategori mental (Burke, 2001:
178).
4. Hubungan Sejarah dengan Psikologi
Dalam cerita sejarah, aktor atau pelaku sejarah
senantiasa mendapat sorotan yang tajam, baik sebagai
individu maupun sebagai kelompok. Sebagai aktor
individu, tidak lepas dari peranan faktor-faktor
internal yang bersifat psikologis, seperti motivasi,
minat, konsep diri, dan sebagainya yang selalu
berintraksi dengan faktor-faktor eksternal yang
bersifat sosiologis, seperti lingkungan keluarga,
lingkungan sosial budaya, dan sebagainya. Begitu pun
dalam aktor yang bersifat kelompok menunjukkan
aktivitas kolektif, yaitu suatu gejala yang menjadi
objek khusus psikologi sosial. Dalam berbagai peristiwa
sejarah, perilaku kolektif sangat mencolok, antara lain
sewaktu ada huru hara, masa mengamuk (mob), gerakan
12
sosial, atau protes revolusioner, semuanya penjelasan
berdasarkan psikologi dari motivasi, sikap, dan
tindakan kolektif (Kartodirdjo, 1992: 139). Di situlah
psikologi berperan untuk mengungkap beberapa faktor
tersembunyi sebagai bagian proses mental.
Sampai sejauh ini, peranan ilmu psikologi dalam
pembahasan sejarah masih agak marginal. Alasanya
terletak pada relasi antara psikologi dengan ilmu
sejarah. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, dua sejaran
Prancis March Bloch dan Lucien Febre menyebarluaskan
praktik-praktik historical psychology ‘psikologi
sejarah’. Setelah Erik Erikson, pengikut Freud
melakukan pengkajian sejarah yang dilakukan secara
psikoanalitis terhadap tokoh sejarah, ternyata
menimbulkan perdebatan sengit.
Pada tahun 1940-an, ada usaha kembali untuk
mendekatkan disiplin sejarah dengan psikologi, terutama
sintesis pandangan Karl Marx dan Sigmund Freud oleh
Erich Fromm, dan kajian kolektif tentang kepribadian
otoriter yang dipimpin oleh Theodor Adorno (Fromm,
1942; Adorno, 195). Relevansi kedua disiplin itu bagi
sejarah adalah penting karena bertolak pada asumsi
“jika kepribadian dasar berbeda-beda pula antarasatu
masyarakat dan masyarakat lainnya, pastilah ia berbeda-
beda pula antara satu periode dan periode lainya”.
Selain itu , pendekatan psikologis paling tidak dapat
dilakukan dengan tiga cara.
13
Pertama, sejarawan terbebas dari asumsi yang hanya
berdasarkan akal sehat tentang sifat manusia (Burke,
2001: 172-174). Kedua, teori para ahli psikologi
memberikan sumbangan pada proses kritik sumber. Agar
autobiografi atau buku harian dapat digunakan secara
tepat sebagai bukti sejarah, perlu dipertimbangkan usia
sang penulis, posisinya dalam siklus kehidupan, maupun
catatan mimpi-mimpinya (Erikson, 1958: 701-702).
Ketiga, ada sumbangan dari para ahli psikologi bagi
sejarah, yakni para psikologi telah banyak memberi
perhatian pada “psikologi pengikut” di samping pada
“psikologi pemimpin”. Di samping itu, beberapa ahli
psikologi pun telah membahas hubungan antara apa yang
disebut aspek psikologistik motivasi dengan aspek
sosiologistik motivasi. Dengan kata lain, apa yang ada
dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai motif publik
dan motif pribadi (Burke, 2001: 174).
5. Hubungan Sejarah dengan Geografi
Hubungan ini dapat dilihat dari suatu aksioma
bahwa setiap peristiwa sejarah senantiasa memiliki
lingkup temporal dan spasial (waktu dan ruang), di mana
keduanya merupakan faktor yang membatasi fenomena
sejarah tertentu sebagai unit (kesatuan), apakah itu
perang, riwayat hidup, kerajaan, dan lain sebagainya
(Kartodirdjo, 1992: 130).
Mengenai kedekatan ilmu geografi dan sejarah
tersebut, ibarat sekutu lama sejak zaman geografiwan
14
dan sejarawan Yunani kuno Herodotus. Menurutnya,
sejarah dan geografi sudah demikian terkait, ibarat
terkaitnya pelaku, waktu, dan ruang secara terpadu.
Para sejarawan kini dapat mempertimbangkan teori daerah
pusat (central place theory), teori difusi inovasi
ruang (spatial diffusion of innovation), maupun teori
ruang sosial (social space) (Hagersrand, 1982;
Buttimer, 1971). Kita hidup si era yang tidak tegas
tentang garis-garis damarkasi disiplin ilmu dan
terbukanya batas ranah intelektual, suatu zaman yang
mengasyikkan skaligus membingungkan. Rujukan kepada
Ellsworth Huntington, Mikhail Bakhtin, Piere Bourdieu,
Fernan Braudel, Michael Foucault, dan sebagainya dapat
ditemukan pada tulisan-tulisan arkeolog, sejarah,
maupun geografi.
Dengan demikian, jelaslah bahwa peranan spasial
dalam geografi distrukturasi berdasarkaan fungsi-fungsi
yang dijlankan menurut tujuan ataukepentingan manusia
selaku pemakai. Kemudian, unit-unit fisik yang dibangun
menjadi unsur struktural fungsional dalam sistem
tertentu, ekonomi, sosial, politik, dan kultural.
Sedangkan struktur dan fungsi itu bermakna dalam
konteks tertentu, yaitu tidak lepas dari jiwa zaman
atau gaya hidup masanya. Dengan demikian, peranan
menjadi kesaksian strukur dalam kaitannya dengan priode
waktu. Di sini hubungan dimensi geografi dengan sejarah
yang tidak dapat dipisah-pisahkan secara kaku.
15
6. Hubungan Sejarah dengan Ilmu Ekonomi
Walaupun kita tahu bahwa sejarah politik pada dua
atau tiga abad terakhir begitu dominan dalam
historiografi Barat, namun ironisnya mulai abad ke-20,
sejarah ekonomi dalam berbagai aspeknya pun semakin
menonjol, terutama setelah proses modrenisasi, di mana
hampir setiap bangsa di dunia lebih memfokuskan
pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, proses
industrialisasi beserta transformasi sosial yang
mengikutinya menuntut pengkajian pertumbuhan ekonomi
dari sistem produksi agraris ke sistem produksi
industrial ( Kartodirdjo, 1992: 136).
Terbentuknya jaringan navigasi atau transformasi
perdagangan di satu pihak dan pihak lain, serta
jaringan daerah industri dan bahan mentah mengakibatkan
munculnya suatu sistem global ekonomi. Lahirnya sistem
global ekonomi tersebut memiliki implikasi yang sangat
luas dan mendalam, tidak hanya pada bidang ekonomi
saja, tetapi erat hubungannya dengan bidang lain,
misalnya bidang politik. Hal itu tampak dengan
pertumbuhan kapitalisme, mulai dari kapitalisme
komersial, industrial, hingga finansial. Ekspansi
politik yang mendukungnya, mengakibatkan timbulnya the
scramble for colonies, persaingan tidak sehat yang
menjurus ke konflik politik dan perebutan jajahan,
singkatnya makin merajalelanya imperialisme
( Kartodirdjo, 1992: 137).
16
Sepanjang masa modren, yaitu lebih kurang sejak
1500, kekuatan-kekuatan ekonomis yang sentripetal
mengarah ke pemusatan pasar dan produksi ke Eropa
Barat, suatu pola perkembangan yang hingga Perang Dunia
II masih tampak. Dari pertumbuhan sistem ekonomi global
yang kompleks itu menurut Kartodirdjo (1992: 137) dapat
dieksplorasikan beberapa tema penting, antara lain:
a) Proses perkembangan ekonomi (economic development)
dari sistem agraris ke sistem industrial, termasuk
organisasi pertanian, pola perdagangan lembaga-
lembaga keuangan, kebijaksanaan komersial, dan
pemikiran (ide) ekonomi.
b) Pertumbuhan akumulasi modal mencakup peranan
pertanian, pertumbuhan penduduk, dan peranan
perdagangan internasional.
c) Proses industrialisasi beserta soal-soal perubahan
sosial.
d) Sejarah ekonomi yang bertalian erat dengan
permasalahan ekonomi, seperti kenaikan harga,
konjungtur produksi agraris, ekspansi perdagangan,
dan sebagainya.
e) Sejarah ekonomi kuantitatif yang mencakup antara
lain Gross National Product (GNP) per capita income.
Perkembangan sejarah ekonomi mengalami pula
difrensiasi dan supspesialisasi, antara lain dengan
timbulnya ejarah pertanian, sejarah kota, sejarah
bisnis, sejarah perburuhan, sejarahnformasi kapital.
17
7. Hubugan Sejarah dengan Ilmu Politik
Politik adalah sejarah masa kini, dan sejarah
adalah politik masa lampau. Dalam hal ini, menunjukkan
bahwa sejarah sering diidentikkan dengan politik,
sejauh ini keduanya menunjukkan proses yang mencakup
keterlibatan para aktor dalam intraksinyaserta
peranannya dalam usaha memperoleh “apa”, ”kapan”, dan
“bagaimana” (Kartodirdjo,1992: 148-149).
Di zaman sekarang, sebenarnya sejarah politik
masih cukup menonjol. Tetapi sedominan masa lampau. Hal
itu sangatmenarik bahwa pengaruh ilmu politik dan ilmu-
ilmu sosial sungguh besar dalam penulisan sejarah
politik yang lebih tepat disebut sejarah politik gaya
baru.
Otoritas dan struktur kekuasaan sangat dipengaruhi
oleh orientasi nilai-nilai dan pandangan hidup para
pelaku sejarah. Dengan demikian, kerangka
konseptualnilmu politik menyediakan banyak alat untuk
menguraikan berbagai unsur politik, aspek politik,
kelakuan aktor, nilai-nilai yang melembaga sebagai
sistem politik, dan lain sebagainya (Kartodirdjo, 1992:
150).
18
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Ilmu sejarah adalah ilmu tentang masa lampau yaang
memiliki metode-metode: (1) heuristik (pengumpulan
sumber-sumber); (2) kritik atau analisis sumber
(eksternal dan internal); (3) interpretasi; (4)
historiografi (peulisan sejarah). Sementara itu sejarah
19
juga memiliki ilmu-ilmu bantu seperti: Paleontologi,
arkeologi, paleontropologi, paleografi, epigrafi,
ikonografi, numisnatik, ilmu keramik, genealogi,
filologi, bahasa, statistik, dan etnografi.
Sementara itu, hubungan ilmu sejarah dengan ilmu-
ilmu yang lain seperti, hubungan ilmu sejarah dengan
ilmu sosiologi, hubungan ilmu sejarah dengan ilmu
antropologi, hubungan ilmu sejarah dengan antropologi
budaya, hubungan ilmu sejarah dengan ilmu psikologi,
hubungan sejarah dengan ilmu geografi, hubungan sejarah
dengan ilmu ekonomi, dan hubungan ilmu sejarah dengan
ilmu politik.
3.2. Saran
Dalam mempelajari sebuah ilmu, dalam hal ini ilmu
sejarah kita harus melihat bagaimana metode-metode
dalam ilmu tersebut, ilmu apa saja yang menjadi ilmu
bantu dari ilmu sejarah, serta kita harus mengetahui
hubungan dari ilmu sejarah dengan ilmu yang lain.
Dalam belajar sejarah kita harus memperhatikan
semua itu, supaya pemahaman kita tentang sejarah lebih
baik, dan kita bisa melestarikan atau mengembangkan
ilmu sejarah tersebut.
20