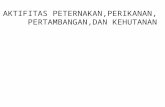manajemen pengembangan peternakan
Transcript of manajemen pengembangan peternakan
PROBLEMATIKA PENGEMBANGAN KERBAU DI INDONESIA
TUGAS:
MANAJEMEN PEMBIBITAN TERNAK
(Problematika Perkembangan Kerbau Di Indonesia)
NAMA : ALIFUDN POY
STAMBUK : DIB4 09 028
JURUSAN PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HALUOLEO
KENDARI
2012
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kerbau (Bubalus bubalis) yaitu ruminansia besar yang
mempunyai potensi tinggi dalam penyediaan daging. Peranan
ternak kerbau cukup signifikan dalam menunjang program
swasembada daging sapi (termasuk kerbau) tahun 2014, dilihat
dari jumlah populasi kerbau sebanyak 2, 2 juta ekor dan
dihasilkan produksi daging sebesar 46 ribu ton atau sebesar 2
% dari jumlah produksi daging nasional, sedangkan kontribusi
daging kerbau sebesar 19 %. Dengan demikian ternak kerbau juga
mendukung penyediaan daging di Indonesia.
Produktivitas kerbau yang berasal dari pemeliharaan
tradisional oleh masyarakat petani memiliki kegunaan sebagi
hewan kerja, sumber daging, pupuk organik dan perlengkapan
acara keagamaan, memegang peranan penting dalam produktivitas
kerbau secara nasional. Pemeliharaan kerbau yang merupakan
integrasi antara faktor biologi, sosiologi dan ekologi akan
mempertahankan kelangsungan produktivitas usahatani. Lahan
pertanian akan tergarap dengan baik karena tenaga kerbau
sebagai pembantu dalam mengolah lahan, pupuk kandang akan
membantu menyuburkan tanah sehingga dapat mempertahankan
produksi padi yang pada giliranya ketahanan pangan akan
tercapai (Bandiati, 2005).
Perkawinan kerbau berkerabat dekat (inbreeding) pada sistem
pemeliharaan kerbau secara ekstensif diduga sebagai penyebab
lain menurunya performa kerbau. Oleh sebab itu perlu adanya
upaya peningkatan produktivitas kerbau melalui program
pemuliaan yang berkelanjutan. Martojo (2004) mengungkapkan
kebutuhan akan adanya suatu rancangan program pemuliaan ternak
nasional telah lama dirasakan. Beberapa gagasan telah diajukan
sejak Repelita I sampai VI oleh Direktorat Jendral Peternakan
untuk setiap Repelita. Demikian pula gagasan atau saran yang
disampaikan para penasehat maupun pakar perguruan tinggi
negeri, pusat penelitian dan pengembangan peternakan yang
bertindak sebagai penasihat bagi DitJenNak dalam kesempatan
berbagai lokakarya yang bersifat umum, menyeluruh ataupun
khusus untuk satu komoditas seperti lokakarya pengembangan
ternak perah, ternak daging dan kerja, dan ternak kecil.
Bentuk lain pula tugas yang dikontrakan kepada beberapa orang
pakar/ahli dari UNPDP/FAO atau biro konsultan. Akan tetapi
sampai dengan orde reformasi sekalipun kegiatan pemuliaan
ternak di Indonesia belum dapat berjalan secara optimal.
Salah satu tolok ukur meningkatnya efisiensi reproduksi
pada ternak kerbau adalah meningkatnya angka kelahiran yang
sangat ditentukan oleh kesubauran betina dan kesuburan
pejantan melalui suatu perkawinan. Perkawinan tidak pernah
akan terjadi bila salah satu dari dua jenis kelamin tersebut
tidak tersedia, baik betina maupun pejantan sehingga tidak
akan terjadi kebuntingan apalagi kelahiran. Walaupun demikian,
masih ada kepercayaan dikalangan sebagian para petani yang
berpendapat bahwa betina dewasa akan bunting meskipun tidak
ada pejantan.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas maka dapat menjadi rumusan
masalah adalah bagaman cara meningkatkan produktifitas ternak
kerbau di Indonesia dalam hal manajemen pemeliharaan, sistem
perkawinan, pemilihan pejantan dan faktor eksternal maupun
faktor internal
C. Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari makalah ini yaitu dapat mengetahui kendala
peningkatan produktifitas ternak kerbau di Indonesia baik
dalam sistem manajemen pemeliharaan, sistem perkawinan maupun
faktor eksternal dan internal.
Manfaat dari makalah ini yaitu dapat mengetahui
perkembangan/peningkatan populasi ternak kerbau di Indonesia
dalam hal manajemen secara umum.
BABA II
PEMBAHASAN
A. Potensi Pengembangan Kerbau
potensi ternak asli daerah yang merupakan sumber plasma
nutfah perlu dijaga dan dilestarikan, salah satunya
adalah pengembangan ternak kerbau rawa sebagai usahatani pada
agroekosistem lahan rawa dengan ”sistem kalang”. Kalang
adalah kandang yang dibuat dari balokbalok/ glondongan kayu
blangiran (shore balangeran) dengan diameter 10-20 cm
yang disusun teratur berselang-seling dari dasar rawa sampai
tersembul diatas permukaan air dengan tinggi ± 2-5 meter,
panjang mencapai 25 meter dan lebar 10 meter, atau
ukuran kalang disesuaikan dengan jumlah kerbau yang ada.
Bagian atas dibuatkan lantai dari belahan kayu yang disusun
rapat untuk kerbau beristirahat. Umumnya kalang
dapat berbentuk empat persegi panjang atau letter L/T, yang
terdiri atas beberapa ancak (petak kalang) dan setiap ancaknya
berukuran 5x5 meter. Pada bagian sisi kalang dibuatkan tangga
untuk turun dan naiknya kerbau, selebar ± 2,5 meter.
Selanjutnya setiap ancak mampu menampung 10-15 ekor
kerbau dewasa. Luas wilayah Kalimantan Selatan 3.503.052 ha de
ngan kondisi agroekosistem lahan kering, pasang surut, lebak,
tadah hujan, rawa dan lainnya; jumlah penduduk
sebanyak 3.201.962 jiwa, dengan mata pencahariannya sebagian
besar dari pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan
peternakan (Badan Pusat Statistik, 2004).
B. Masalah Pengembangan Kerbau Di indonesia
Faktor penyebab menurunnya populasi kerbau di Indonesia
tidak jauh berbeda dengan di negara-negara Asia lainnya.
Penurunan produktivitas kerbau disebabkan faktor internal dan
faktor eksternal.
1. Faktor internal
Faktor internal ditentukan oleh sifat atau karakteristik
dari suatu jenis ternak. Pada kerbau sifat internal yang
berpengaruh terhadap kendala peningkatan populasi adalah:
Masak lambat
Kerbau termasuk ternak yang lambat di dalam mencapai
dewasa kelamin (SUBIYANTO, 2010). Pada umumnya kerbau
mencapai pubertas pada usia yang lebih tua, sehingga kerbau
mencapai dewasa kelamin pada usia minimal 3 tahun (TOELIHERE,
1985; DO KIM TUYEN dan NGUYEN VAN LY, 2001); 2 – 3 tahun
(LENDHANIE, 2005); 2 – 2,5 (SUBIYANTO, 2010).
Lama bunting
Kerbau akan mengandung anaknya selama 10,5 bulan,
sedangkan sapi hanya 9 bulan. Menurut KEMAN (2006) lama
bunting pada kerbau bervariasi dari 300 – 334 hari (rata-
rata 310 hari) atau secara kasar 10 bulan 10 hari.
Dikemukakan pula oleh HILL (1988) bahwa N lama bunting pada
kerbau lebih lama dan lebih bervariasi. Untuk kerbau kerja
lama bunting kerbau di Mesir bervariasi dari 325 sampai
330 hari. Hasil penelitian LANDHANIE (2005) di Desa
Sapala, Kecamatan Danau Panggang lama bunting kerbau rawa
mencapai 1 tahun.
Berahi tenang
Tanda-tanda berahi pada kerbau, umumnya tidak tampak
jelas (SUBIYANTO, 2010). Sifat ini menyulitkan pada
pengamatan berahi untuk program inseminasi buatan. Meskipun
fenomena ini bisa diatasi dengan menggunakan jantan, namun
kelangkaan jantan dan sistem pemeliharaan yang terkurung
memungkinkan perkawinan tidak terjadi.
Waktu berahi
Umumnya berahi pada kerbau terjadi pada saat menjelang
malam sampai agak malam dan menjelang pagi atau saat subuh
atau lebih pagi (TOELIHERE, 2001). Menurut HILL (1988)
tanda-tanda berahi dan aktivitas perkawinan pada kerbau di
Mesir umumnya pada kerbau terjadi pada malam hari. Pada saat
seperti ini umumnya kerbau-kerbau betina di Indonesia sedang
berada dalam kandang yang tertutup, yang tidak memungkinkan
terjadinya perkawinan.
Jarak beranak yang panjang
Jarak beranak yang panjang merupakan implikasi dari
sifat-sifat reproduksi lainnya. Pada kerbau kerja jarak
beranak bervariasi dari 350 sampai 800 hari dengan rata-rata
553 hari (KEMAN, 2006). Menurut HILL (1988) jarak beranak
pada kerbau bervariasi dari 334 hari sampai 650 hari,
tergantung pada manajemen
yang dilakukan. Menurut LADHANIE (2005) jarak beranak
pada kerbau rawa antara 18 sampai 24 bulan.
Beranak pertama
Panjang sifat-sifat produksi lain akan berpengaruh
langsung terhadap beranak pertama pada kerbau. Hasil survei
di Indonesia terutama di NAD, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Selatan, umur pertama kali
kerbau beranak masing-masing 45,0; 49,6; 47,7; 49,1; 45,6
dan 49,2 bulan dengan rata-rata 47,7 bulan (ANONIMUS,
1985 yang dikutip KEMAN, 2006). Sementara itu, di Brebes,
Pemalang, Semarang dan Pati rata-rata umur kerbau pertama
kali beranak, berturutturut adalah 44, 40, 44 dan 42
bulan (SURYANTO, et al. 2002 yang dikutip KEMAN, 2006).
2. Faktor eksternal
Diantara faktor eksternal, ada yang berpengaruh langsung
terhadap performan reproduksi dan ada yang berpengaruh tidak
langsung. Reproduksi adalah suatu proses yang rumit pada
semua species hewan. Rumit karena reproduksi tergantung
pada fungsi yang sempurna proses- proses biokimia dari
sebagian besar alat tubuh. Ovulasi, birahi, kebuntingan,
kelahiran dan laktasi, itu semua tergantung dari
fungsi yang sempurna dari berbagai hormone dan alat
tubuh. Setiap abnormalitas dalam anatomi atau fisiologi dari
alat reproduksi berakibat fertilitas menurun atau dapat
menyebabkan sterilitas (ANGGORODI, 1979). Faktor
eksternal yang berpengaruh langsung terhadap performa
reproduksi adalah:
Pakan
Kontribusi pakan sangat kuat pengaruhnya terhadap performan
reproduksi. Makanan berperan penting dalam perkembangan
umum dari tubuh dan reproduktip (TILLMAN et al., 1983).
Peternak kerbau di negara kita pada dasarnya merupakan
peternak tradisional dan merupakan kegiatan yang turun menurun
sehingga pemberian pakan umumnya di dapat pada saat
digembalakan. Rumput yang tumbuhdi lapangan, di pematang sawah
atau pinggirpinggir jalan adalah pakan yang tersedia pada saat
digembalakan. Pakan yang diberikan di kandang umumnya jerami
kering yang kadang-kadang disiram larutan garam dapur. Pada
musim kemarau ketersediaan rumput alam akan sangat menurun
jumlahnya dan secara langsung akan berpengaruh terhadap asupan
pakan pada ternak. Pakan dengan kualitas dan kuantitas seperti
ini akan berpengaruh tidak baik terhadap performa reproduksi.
Diperparah lagi oleh tugas yang harus dilakukan pada saat
musim mengolah sawah. Meskipun salah satu keunggulan kerbau
adalah mampu memanfaatkan pakan dengan kualitas rendah, namun
untuk mendapatkan performan reproduksi yang baik memerlukan
makanan yang cukup, baik kualitas maupun kuantitas.
Sosial budaya
Beberapa daerah di Indonesia yang secara sosial budaya
berkaitan dengan kerbau menunjukkan populasi kerbau yang
tinggi. Keterkaitannya bisa berupa dalam adat istiadat atau
kebutuhan tenaga kerja. NTB, Sumatera Barat, Sumatera Utara,
Sulawesi Selatan keterkaitannya lebih pada adat istiadat
yang turun temurun. Di Sumatera Barat, kerbau mempunyai arti
sosial yang sangat khas. Rumah adat dan perkantoran
pemerintah mempunyai bentuk atap yang melengkung
melambangkan bentuk tanduk kerbau. Diduga kata
“Minangkabau” berasal dari “Menang Kerbau (HARDJOSUBROTO,
2006). Pada masyarakat Batak dikenal upacara kematian
seperti saur matua dan mangokal hili. Bagian dari rangkaian
upacara tersebut biasanya dilaksanakan pesta syukuran
adat yang disertai pemotongan kerbau. Pemotongan kerbau juga
dilakukan pada saat upacara perkawinan, horja bius (acara
penghormatan terhadap leluhur, dan pendirian rumah adat
(SUSILOWATI, 2008). Bagi etnis Toraja, khususnya Toraja
Sa’dan, kerbau adalah binatang paling penting dalam
kehidupan sosial mereka (NOOY-PALM, 2003 yang dikutip
STEPANUS, 2008) Selain sebagai hewan untuk memenuhi
kehidupan sosial, ,ritual maupun kepercayaan tradisional,
kerbau juga menjadi alat takaran status sosial dan alat
transaksi. Dari sisi sosial, kerbau merupakan harta yang
bernilai tinggi bagi pemiliknya (ISSUDARSONO, 1976 yang
dikutip STEPANUS, 2008). Kerbau juga merupakan hewan
domestik yang sering dikaitkan dengan kehidupan masyarakat
yang bermata pencaharian di bidang pertanian. Di Banten,
kerbau selain digunakan sebagai hewan kerja juga
masyarakatnya sangat fanatic terhadap daging kerbau. Menurut
PATHERAM dan LIEM (1982) selera masyarakat Banten
terhadap daging kerbau cukup tinggi dibandingkan dengan
daging sapi. Di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur lebih
pada kebutuhan tenaga kerja. Hal ini menunjukan bahwa
budaya masyarakat sangat berperan terhadap perkembangan
populasi kerbau. Populasi kerbau di Indonesia terdapat di
seluruh provinsi, karena kerbau mempunyai daya adaptasi
yang sangat tinggi. Kerbau bisa berkembang mulai dari
daerah kering di NTT dan NTB, lahan pertanian yang subur
di Jawa hingga lahan rawa di Sulawesi Selatan, Kalimantan
dan daerah pantai utara Sumatera (Asahan sampai Palembang).
Selain itu pengembangannya juga tidak akan menghadapi
hambatan selera, budaya dan agama (TRIWULANNINGSIH). Pada
Tabel 1 memperlihatkan sepuluh propinsi yang memiliki
jumlah kerbau terbanyak di Indonesia.
C. Manejemen Perkawinan
Bagi daerah–daerah dengan imbangan jantan dan betina
sempit, maka IB bukanlah prioritas utama dalam melaksakan
sistem perkawinan. Diketahu bahwa tingkat kebuntingan hasil IB
masih cukup rendah yakni sekitar 30% pada kondisi lapangan dan
pada kondisi stasiun percobaan 60% (SITUMORANG dan SITEPU,
1991). IB hendaknya dilakukan pada wilayah dimana kerbau
jantan jumlahnya terbatas, seperti di Tana Toraja dan
Kalimantan Selatan. Kiranya akan lebih bijaksana bila sistem
perkawinan yang diterapkan adalah kawin alam secara kelompok
dalam kandang kelompok dengan imbangan jantan : betina = 1 :
10, karena dengan sistem perkawinan ini peternak tidak repot
untuk mengamati berahi, pejantan dengan sendirinya dapat
mengetahui kerbau betina yang berahi dan secara otomatis akan
mengawininya
Diketahui, walaupun perkawinan menggunakan sistem IB,
namun dibutuhkan juga pejantan untuk kawin alam, hal ini
dimaksudkan bila terjadi kegagalan dalam menggunakan IB karena
berahi tenang, maka pejantan tersebut dapat mengawini betina–
betina yang mengalami berahi tenang tersebut sebagaimana biasa
dilakukan pada ternak sapi perah. JILL (2006) menerangkan
bahwa pada sekelompok sapi perah induk yang berjumlah 600–800
ekor sistem perkawinan menggunakan IB selama 6 minggu,
selebihnya dilakukan kawin alam dengan menggunakan pejantan
untuk mengawini sapi perah indukyang mengalami berahi tenang.
Jumlah pejantan yang digunakan adalah 4 ekor dengan perincian
3 ekor untuk 100 betina dan 1 ekor pejantan lagi sebagai
cadangan. Pejantan disatukan dengan betina dalam kandang
kelompok selama 12 minggu.
D. Program Seleksi dalam Bangsa
Seleksi dilakukan oleh petugas teknis pendamping
Kabupaten terhadap ternak yang akan dikembangkan untuk
keperluan peremajaan atau dijual sebagai bibit. Seleksi calon
bibit betina dipilih 50% dan calon bibit jantan 20% terbaik
dari hasil keturunan untuk menghasilkan bibit yang memenuhi
kriteria mutu. Sifat kuantitatif induk kerbau yang perlu
diperhatikan dalam seleksi adalah : Umur pubertas (2 tahun),
kelahiran yang teratur (calving interval teratur), bobot
lahir, bobot sapih, bobot kawin, bobot dewasa, laju
pertumbuhan setelah disapih dan produksi susu. Sifat
kualitatif induk kerbau yang perlu diperhatikan dalam seleksi
adalah : bentuk tubuh/eksterior.ada tidaknya cacat, tidak ada
kesulitan melahirkan dan tabiat (behavior).
Martojo (1989) menyarankan program seleksi dalam bangsa
yang dapat dilaksanakan dalam kelompok peternak dengan
ternaknya secara sederhana
dipedesaan. Secara sederhana tanpa catatan dalam bentuk
recording di atas kertas
dianjurkan untuk melaksanakan “catul” atau catatan berulang
yang dicatat dalam
bentuk cap bakar pada tubuh ternak, dalam hal ini induk dan
anaknya. Satu catatan yang diperlukan yaitu bobot sapih atau
bobot pada sekitar 6-7 bulan. Jika tidak ada timbangan dapat
dengan mengukur lingkar dada saja. Ukuran lingkar dada tidak
perlu diterjemahkan ke dalam taksiran bobot badan. Ukuran ini
hanya dipakai untuk membandingkan satu anak ternak (kerbau)
dari yang lain dalam kelompok umur dan daerah yang sama. Anak
kerbau yang merupakan 10-20% terbaik ditetapkan sebagai bibit
pilihan dan diberi cap bakar A seterusnya kelompok B adalah
yang merupakan sisa yang berukuran di atas rataan kelompoknya.
Induk dari anak kerbau kelas A diberi cap A pula. Selanjutnya
bibit pilihan jantan dan betina dijadikan calon pejantan dan
induk untuk menghasilkan generasi selanjutnya. Martojo (2002)
mengungkapkan bahwa upaya perubahan genetik hewan sejak masa
penjajahan sampai masa kemerdekaan tidak menunjukkan hasil
yang memadai, karena upaya pemuliaan ditekankan pada impor
bahan genetik dari luar untuk dipelihara sebagai bangsa hewan
murni atau persilangan.
Upaya melalui seleksi tidak banyak dilakukan terutama
dalam pelita I sampai VI yang lalu, hal ini karena perencanaan
yang ditekankan pada pemerataan dan cara-cara relatif murah
dengan hasil cepat dan menonjol. Ketika arus bioteknologi
melanda dunia, Indonesia harus sanggup melaksanakan penelitian
rekayasa genetik sebatas embrio transfer dan beberapa teknik
manipulasi seluler embrio. Upaya seleksi yang sejak itu sudah
dianggap rekayasa genetik konvensional, yang seharusnya
menjadi dasar bagi rekayasa genetik modern, justru dianggap
tidak perlu diprioritaskan, sehingga ketertinggalan
dalam bidang ini sampai saat ini semakin jauh. Bahwa rekayasa
genetik modern
terutama dalam rekayasa pembentukkan hewan transgenik ternyata
menghadapi
berbagai kendala, bagi bidang pemuliaan hewan disambut dengan
rasa yang lega
karena, dengan demikian diharapkan pemuliaan atau rekayasa
konvensional dapat
menyusul ketertinggalannya dan langsung turut menunjukkan
perhatian pada bidang bioteknologi molekuler untuk tujuan
seleksi terbantu penciri (marker asisted selection /MAS). Untuk
seleksi model terakhir ini, misalnya pada peternakan sapi
potong/daging, sangat diperlukan berkembangnya subsistem
industri peternakan berupa usaha peternakan pembibitan (tempat
pemuliaan konvensional diterapkan), subsistem usaha peternakan
bakalan dan subsistem penggemukan. Pada akhir orde
pemerintahan yang lalu hanya sub sistem penggemukkan yang
didukung pemerintah, sedangkan upaya lain ditekankan pada
bentuk peternakan rakyat, yang tidak memungkinkan pemuliaan
konvensional di dalamnya.
Lebih jauh Martojo (2002) mengungkapkan bahwa penelitian
bidang
pemuliaan ternak konvensional di lembaga penelitian di
lingkungan Depertemen
Pertanian dan perguruan tinggi di Departemen Pendidikan
Nasional selama itu tidak cukup dana untuk pelaksanaan
penelitian jangka panjang untuk pembentukan bangsabangsa
ternak unggul. Pihak swasta sementara itu tidak tertarik untuk
berusaha dalam bidang pembibitan, apalagi penelitian dalam
bidang pemuliaan ternak konvensional. Akibatnya terlihat dari
kenyataan bahwa, berbeda kontras dengan bidang pemuliaan
tanaman konvensional, sampai saat ini belum berhasil dibentuk
satupun bangsa hewan unggul setara varietas, klon atau bibit
unggul dalam bidang tanaman pangan, hortikultura atau
perkebunan. Ironis bahwa pada saat BAPPENAS/DRN merestui
pemanfaatan sejumlah dana besar untuk penelitian dalam bidang
peternakan, pemerintah justru tidak mendukung pelaksanaan
penelitian pemuliaan konvensional tetapi mau membuat lompatan
langsung ke bidang bioteknologi. Hal ini masih terus terjadi
hingga era reformasi dan krisis moneter yang berkepanjangan
ini semakin tidak mungkin realisasi penelitian pemuliaan
konvensional.
E. Pemuliaan Ternak Berkelanjutan
Pemuliaan ternak berkelanjutan diimplementasikan dalam
kesinambungan
program dan tujuan pemuliaan yang paripurna secara terus
menerus sehingga
dihasilkan ternak yang berkualitas genetik tinggi dan
responsif terhadap teknologi.
Philipsson dan Rege (2002) menyatakan, kegiatan pemuliaan
ternak tidak semata-mata hanya menerapkan teori tentang
pemuliaan ternak untuk meningkatkan
produktivitasnya, akan tetapi berkaitan erat dengan
pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dengan memperhatikan
kesempatan peningkatan kesejahteraan dari ternak yang
dimilikinya. Oleh karenanya program pemuliaan ternak erat
kaitannya dengan aspek: (i) kebijakan pemerintah (ii) peran
peternak, (iii) infrastruktur (saranaprasarana), dan (iv)
kesesuaian genotipe dengan lingkungan sehingga sumberdaya
ternak yang tersedia cocok dengan lingkungannya.
Potensi sumberdaya peternak dan lingkungan pendukung
dapat menjadi
rujukan rencana implementasi program pemulian ternak yang akan
dilakukan. Kosgey (2004) memaparkan bahwa walaupun peternakan
rakyat melakukan kegiatan usahaternak secara tradisional,
namun sumbangannya terhadap perbaikan mutu genetic ternak
cukup besar, karena mereka dengan segala kelebihan dan
kekuranganya mampu memilih dan memilah ternak yang dipelihara
sesuai dengan kondisi lingkungan serta sosial budayanya. Peran
serta peternak dalam kegiatan pemuliaan ternak sangat
diperlukan, karena keinginan dan harapan peternak untuk
memperoleh ternak bermutu genetik baik yang cocok dengan
lingkungannya merupakan landasan kuat pentingnya dilakukan
kegiatan pemuliaan ternak. Hal ini sejalan dengan pendapat
Wollny et al. (2002) yang menyatakan bahwa kegagalan pemuliaan
ternak di negara berkembang disebabkan bersifat top down tanpa
memperhatikan dan melibatkan kepentingan peternak.
Chantalakana dan Skunmun (2002) mengungkapkan kendala
kegiatan
pemuliaan ternak di negara berkembang adalah rendahnya
dukungan pemerintah
(finansial maupun kebijakan). Implikasinya adalah kegiatan
pemuliaan ternak kurang dapat berjalan dengan baik, padahal
konsep peternakan yang berkelanjutan
menghendaki adannya dukungan kerjasama semua fihak terkait
(peternak, pemerintah, peneliti, praktisi dan akademisi)
sedemikian rupa sehingga kegiatan peternakan memberikan
manfaat bagi seluruh generasi yang diwujudkan dengan
terjaganya kualitas lingkungan hidup yang baik.
Langkah pertama pada kegiatan pemuliaan ternak adalah
menentukan tujuan pemuliaan (breeding objective) dan pola pemuliaan
(breeding strategies). Tujuan dan pola pemuliaan harus dirumuskan
dengan jelas oleh para pelaku kegiatan pemuliaan sehingga
dapat diimplementasikan dalam pelaksanaannya (Kosgey, 2004).
Di negara berkembang agraris seperti Indonesia, kerbau lumpur
umumnya digunakan sebagai sumber tenaga kerja pengolah lahan.
Oleh sebab itu tujuan pemuliaan yang mungkin dapat dirumuskan
adalah mendapatkan kerbau lumpur yang unggul sebagai tenaga
pengolah lahan pertanian. Chantalakhana dan Skunmun (2002)
mengungkapkan jika kerbau lumpur akan ditujukan sebagai ternak
kerja pengolah lahan, maka kriteria seleksi yang dapat
dilakukan adalah kekuatan, daya tahan terhadap cekaman panas
dan bertemperamen baik sehingga mudah dikendalikan oleh
peternak.
Komponen yang harus diperhatikan meliputi: kekuatan kaki,
ukuran teracak kaki, kemampuan berjalan, tinggi pundak dan
panjang badan, ketebalan bulu, warna kulit, daya tahan
terhadap parasit tubuh serta cocok dengan kondisi sosial
budaya peternak yang menilainya. Pola pemuliaan kerbau yang
mungkin dapat dilakukan adalah open nucleus breeding, yakni
dimungkinkan adanya aliran gen dari inti dan pembiak. Pola
seperti itu telah dilakukan dalam peningkatan mutu genetik
kerbau di Thailand sejak tahun 1981 melalui The National Buffalo
Breeding and Research Programme. Tujuannya adalah diperoleh kerbau
unggul yang kemudian dapat disebar kepeternak. Para peternak
dilibatkan dalam kegiatan pemuliaan melalui “Cattle and Buffalo Bank
Royal Project”, Development of Livestock Production at Small-Farmer Level’ dan
kemajuan genetik didesiminasikan agar para peternak tidak
menjual kerbau potensial kepada tengkulak untuk dipotong (Na-
Chiangmai, 2000).
Intaramongkol (1998) memberikan ilustrasi kegiatan
pemuliaan kerbau yang dilakukan di Thailand (Surin Buffalo Breeding
Center) (ilustrasi 1). Pada kelompok inti (elite) terdiri atas 15
ekor pejantan dan 300 ekor betina terpilih. Pejantan elite
mengawini betina pada populasi inti, populasi betina di
stasiun pemerintah atau swasata dan betina di peternakan
rakyat. Hasil perkawinan pada stasiun pemerintah atau swasta
akan diperoleh betina terseleksi yang pada akhirnya dijadikan
sebagai betina elite pada populasi inti, sedangkan hasil
perkawinan pada populasi peternakan rakyat dilakukan seleksi
melalui acara kontes ternak yang telah dilakukan sejak tahun
1994, dan juara kontes dipilih sebagi ternak betina terbaik
yang kemudian akan dimasukkan ke dalam kelompok elite pada
populasi inti, begitulah seterusnya.
Dalam program pemuliaan inti terbuka (open nucleus breeding
system, ONBS), aliran gen-gen dari populasi bibit induk
dimungkinkan masuk ke populasi inti yakni dengan penjaringan
ternak betina. Sedangkan aliran gen dari populasi bibit sebar
dapat masuk ke populasi bibit induk juga dilakukan melalui
penjaringan ternak betina sebagai replacement. Betina-betina
terbaik dari populasi bibit induk yang mempunyai performans
diatas rataan populasi inti dapat masuk ke populasi inti.
Sementara itu betina dalam kelompok bibit dasar mempunyai
performans di bawah rataan populasi dipindahkan ke populasi
bibit induk. Pejantan yang dilahirkan dari populasi inti
dipergunakan untuk mengawini betina-betina di populasi bibit
induk atau populasi bibit sebar. Namun demikian tidak
dimungkinkan ada aliran gen (perpindahan pejantan) dari
populasi bibit induk atau populasi bibit sebar ke populasi
inti, kecuali jika ada kondisi yang luar biasa (Diwyanto dan
Hardimirawan, 2006).
F. Upaya-Upaya Inovasi Teknologi
Untuk meningkatkan produktivitas dan eksistensi kerbau
rawa secara berkelanjutan,n Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan melakukan perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan
ternak kerbau,
yang meliputi: 1) peningkatan mutu genetik melalui grading up, 2)
revitalisasi dan pengembangan kawasan perbibitan kerbau rakyat
melalui penataan kelompok, dan 3) pelaksanaan biosekuriti
secara tepat terutama pada kawasan perbibitan. Pengadaan
dan pengembangan bibit kerbau dilakukan melalui seleksi dan
afkir atau culling secara sistematis, dan menyebarluaskan bibit
unggul hasil kajian dan telah memperoleh justifikasi dari
lembaga berwenang, baik di pusat maupun daerah. Program
pemuliabiakan untuk memperoleh bibit unggul dilakukan melalui:
1) seleksi peningkatan populasi dan produktivitas, 2)
persilangan secara sistematis dan terarah, dan 3) program
pencatatan atau recording system terutama di lokasi yang diarahkan
untuk pembibitan dan sertifikasi bibit (Toelihere dan Achyadi
2005). Penelitian dan pengkajian tentang teknologi pakan
dengan pemanfaatan bahan pakan lokal untuk meningkatkan
produktivitas dan reproduktivitas kerbau rawa perlu dilakukan.
Penataan areal penggembalaan alami juga dapat memenuhi
ketersediaan pakan sepanjang tahun.
Pencegahan dan pengendalian penyakit, terutama
fascioliasis, ngorok, surra, dan penyakit lainnya perlu
dilakukan secara periodik. Untuk mengendalikan penyakit ngorok
dapat dilakukan vaksinasi dengan cakupan minimal 60−70%
populasi terancam, pemberantasan vector penyakit, menyiagakan
petugas lapang (tenaga medis veteriner), serta melaporkan bila
terjadi wabah penyakit kepada petugas atau dinas peternakan
terdekat. Jika ada kerbau yang mati dapat dilakukan
pengambilan spesimen untuk pemeriksaan lebih lanjut di
laboratorium. Hewan yang sakit harus segera diobati (Tarmudji
2003).
G. Lahan Penggembalaan
Sistem pemeliharaan ternak kerbau di pedesaan di Jambi
sangat tergantung pada lahan penggembalaan karena sistem
pemeliharaan yang ekstensif tradisional. LUBIS (1999),
melaporkan bahwa 91% pemeliharaan kerbau di Propinsi Jambi
masih
memanfaatkan pakan alami yang diambil sendiri oleh ternak di
padang penggembalaan dan selebihnya diambil secara cut and carry
untuk makan selama masa musim tanam. Pada saat ini umumnya
lahan yang dominan digunakan adalah untuk perkebunan kelapa
sawit dan karet. Sementara itu juga padang penggembalaan telah
banyak beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit dan karet
(Gambar 3). Dengan semakin berkurangnya lahan penggembalaan
maka pada musim kemarau telah mulai kelihatan dampak negative
bagi perkembangan ternak kerbau seperti terjadi beberapa kasus
keguguran (kasus di Desa Mersam). Selain alih fungsi lahan
pengembalaan, statusnya hanya dimiliki oleh individu sehingga
suatu saat nanti lahan penggembalaan semakin berkurang apabila
dibiarkan berlanjut seperti saat ini. Untuk itu diperlukan
kebijakan-kebijakan dalam rangka mempertahankan keberadaan
lahan penggembalaan pada daerah-daerah yang potensial
pengembangan ternak kerbau. Belum adanya lahan penggembalaan
yang legal secara hukum di tingkat pedesaan akan menimbulkan
kekhawatiran beralih fungsinya lahan-lahan tersebut bagi usaha
di luar peternakan.
Untuk mengoptimalkan penggunaan lahan sebenarnya ternak
kerbau dapat diintegrasikan dengan perkebunanan kelapa sawit
dan karet, pada tanaman berusia di atas 6 tahun. Banyak
keuntungan apabila ternak kerbau diintegrasikan dengan
perkebunan sawit dan karet, memanfaatkan rumput yang tumbuh di
antara tanaman utama sebagai pakan dan dijadikan tenaga kerja
untuk alat transportasi
tandan buah segar (TBS) sawit. Sebenarnya kemampuan ternak
kerbau untuk
mengkonsumsi pakan lebih baik dari ternak sapi. DEVENDRA
(1985) mengemukakan bahwa kerbau mampunyai kemampuan lebih
baik memanfaatkan hijauan yang berkualitas rendah dari pada
sapi. menurut beberapa laporan jarak kelahiran adalah 18-24
bulan. Gambar 3 (kasus di Desa Mersam) memperlihatkan bahwa
anak yang diperkirakan berumur 1,5 tahun masih menyusui dengan
induknya, hal ini mengindikasikan reproduksi ternak kerbau di
tingkat petani masih lambat sebagai mana yang dilaporkan oleh
PUTU (1992). Beberapa masalah pengembangan ternak kerbau di
Indonesia antara lain adalah pemasaran daging kerbau,
pertumbuhan yang lambat, calving interval yang panjang
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dari pembahasan diatas maka ditarik suatu kesimpulan
yaitu
1. padang penggembalaan semakin terbatas, mortalitas tinggi
dan penjualan kerbau jantan yang tinggi.
2. Pengembangan kerbau diprioritaskan pada daerah-daerah
yang social budaya masyarakatnya sangat erat kaitannya dengan
kerbau.
3. Pembentukan kelompok peternak kerbau perlu revitalisasi,
untuk memudahkan transfer ilmu dan teknologi yang berkaitan
dengan percepatan peningkatan populasi dan kualitas kerbau.
4. Perlu adanya introduksi pejantan unggul pada kelompok
peternak yang belum memungkinkan dilakukan IB.
5. Produksi semen beku kerbau perlu ditingkatkan di setiap
Balai Inseminasi Buatan.
6. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan inseminator
perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan pusat dan
7. Sifat kerbau yang memperlihatkan berahi tenang sehingga
sulit dilakukan IB harus disiasati dengan melakukan
sikronisasi birahi.
8. meningkatkan populasi dan kualitas kerbau di negeri kita
selain melaksanakan aktivitas untuk menyiasati faktor internal
yang lebih terarah dan berkelanjutan, perlu pula memperhatikan
dan memperbaiki faktor internal yang pengaruhnya sangat kuat.
DAFTAR PUSTAKA
Bandiati, S. 2005. Karakteristik bangsa dan pengembangan
kerbau lokal. Disampaikan pada saresehan peternakan 2005,
revitalisasi ternak kerbau dan pola perbibitan sapi potong.
Bandung 24 Desember 2005.
DitJenNak. 2006. Statistik Peternakan 2006. CV Arena Seni.
Jakarta.
Diwyanto, K. dan E. Hardiwirawan. 2006. Strategi pengembangan
ternak kerbau: Aspek penjaringan dan distribusi.
Prosiding Lokakarya Nasional Usahaternak Kerbau Mendukung
Program Kecukupan Daging Sapi.
Balitbang Deptan Puslitbangnak bekerjasama dengan
Direktorat Perbibitan
DitjenNak, DisPet Provinsi NTB dan Pemda Kab. Sumbawa.
Sumbawa 4-
5 Agustus 2006.
Hardjosubroto, W. 2006. Kerbau mutiara yang terlupakan. Orasi
purna tugas.
Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Kosgey IS. 2004. Breeding objective and breeding strategies
for small ruminants in the tropics. Ph.D. Thesis, Animal
Breeding and Genetics Group. Wageningen University.
Misra, A.K. 2006. Application of embryo biotecnology to
augment reproduction
and production in buffaloes: current status and future
possibilities. Internnational seminar on artificial
reproductive biotechnologies for buffaloes. August 28-
September 01 2006. Bogor-Indonesia.
Philipsson, J. and J.E.O. Rege. 2002. Sustainable breeding
programes for tropial
farming systems. Module 3. Animal genetics training
resources (CDROOM) Version 1 (2002) ILRI-SLU.
Sofyan, A. 2006. Dukungan kebijakan Areal untuk pengembangan
kawasan ternak kerbau. Prosiding Lokakarya Nasional
Usahaternak Kerbau Mendukung Program Kecukupan Daging Sapi.
Balitbang Deptan Puslitbangnak bekerjasama dengan
Direktorat Perbibitan DitjenNak, DisPet Provinsi NTB dan
Pemda Kab. Sumbawa. Sumbawa 4-5 Agustus 2006.
Suryanto, B, M. Arifin, and E. Rianto. 2002. Potential of
swamp buffalo development in Central Java, Indonesia. Buffalo
Bulletin Vol.21 No.1. 3- 9p Toelihere, M. 1975. Physiology of
reproduction and artificial insemination of water buffaloes.
Food and technology center for the Asian and Facific
region.
Triwulaningsih E and L Praharani. 2006. Buffaloes in
Indonesia. International
seminar on artificial reproductive biotechnologies for
buffaloes. August 28-September 01 2006. Bogor-Indonesia.
Wollny CBA, Banda JW, Mlewah TFT, Phoya, RKD. 2002. The lesson
livestock
improvement failure: revising breeding strategies for
indigenous Malawi sheep.In: Proceeding of the seventh World
Congress on Genetics Applied to Livestock Production, vol 33,
Montpellier, France, 19-23 august 2002.