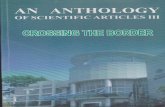Dari lokal ke global: Berfikir kontekstual, indigenous psychology, dan masa depan psikologi...
Transcript of Dari lokal ke global: Berfikir kontekstual, indigenous psychology, dan masa depan psikologi...
Dari lokal ke global:
Berfikir kontekstual, indigenous psychology, dan masa depan psikologi Indonesia di
arena internasional1
Moh. Abdul Hakim
Prodi Psikologi, Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret
Abstrak
Indigenous psychology (IP) merupakan salah satu pendekatan baru dalam
bidang psikologi yang saat ini semakin populer, terutama di kalangan para
akademisi di kawasan Afrika, Pasifik, dan Asia, termasuk Indonesia. Berbeda
dengan psikologi mainstream yang terobsesi dengan teori-teori yang bersifat
universal dan bebas nilai, pendekatan IP justru mendorong para psikolog
untuk mampu berpikir secara kontekstual; memahami perilaku dan proses
mental berdasarkan partikularitas latar dimana keduanya muncul, baik itu
dari segi latar kesejarahan, kultur, agama, sosial-ekonomi, dan lain
sebagainya. Di artikel ini, saya akan memaparkan rangkuman teoritis, hasil
penelitian empiris, dan beberapa gagasan yang bertujun untuk menjawab tiga
pertanyaan berikut, yaitu (i) mengapa kita perlu mengubah cara berfikir dari
pola deduktif ke arah yang lebih kontekstual? (ii) apa relevansi IP dengan
trend penelitian global? Dan, (iii) riset-riset seperti apa yang diperlukan oleh
dunia psikologi di Indonesia agar dapat mendapatkan posisi terhormat di
dalam forum akademik internasional? Saya berharap bahwa tiga hal pokok
yang ingin saya share ini mampu menstimulasi semangat para akademisi muda
untuk melakukan penelitian dengan pendekatan IP dan sekaligus menawarkan
sebuah gagasan alternatif tentang peta riset psikologi Indonesia di masa
depan.
Kata kunci: berfikir kontekstual, indigenous psychology, psikologi Indonesia,
trend riset psikologi global
Mengapa perlu berfikir secara kontekstual?
Setiap kali saya memulai diskusi tentang indigenous psychology (IP), saya selalu teringat
bagaimana Professor Uichol Kim--mentor saya—selalu mengawali uraiannya dengan
1 Makalah ini disusun sebagai bahan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Prodi Psikologi, Universitas Paramadina, tanggal 2 Oktober, Jakarta.
meyakinkan para mahasiswa bahwa berfikir kontekstual merupakan sebuah keniscayaan. Hal
ini mudah dimengerti mengingat cara berfikir kontekstual itu sendiri merupakan kunci dalam
pendekatan IP (Kim & Berry, 1993; Allwood & Berry, 2006; Hwang, 2006). Baik, sekarang
ini saya memilih melakukan cara yang sama.
Bayangkan bola dunia berada di hadapan Anda, ia bersinar biru dengan torehan-torehan
warna hijau dan kelabu di beberapa bagiannya. Bola bumi ini terlihat memantulkan cahaya
matahari dengan indah di tengah ruang gelap alam semesta. Nah, sekarang cobalah Anda
renungkan, apakah Anda sebagai manusia tinggal di bumi dengan kondisi seperti apa adanya
di sana? Ataukah, sebenarnya Anda tinggal di dunia yang Anda kontruksi di dalam pikiran?
Hewan dan tumbuhan tinggal di alam yang mereka terima apa adanya. Mereka hidup dengan
cara merespon setiap stimulasi yang muncul dari lingkungan hidupnya. Untuk bertahan
hidup, mereka melakukan penyesuaian diri. Hewan dan tumbuhan tidak memiliki kesadaran
untuk melakukan proses berfikir dan melakukan evaluasi, dan tidak memiliki intensitas untuk
merespon dengan cara tertentu. Respon hewan dan tumbuhan muncul secara otomatis
sebagaimana digambarkan oleh hukum S-R dalam pendekatan Behaviorisme (Skinner, 1963).
Tentu saja manusia memiliki cara respon terhadap alam semesta yang berbeda dengan hewan
dan tumbuhan. Manusia adalah makhluk yang memiliki kesadaran, yang memungkinkannya
untuk tidak hanya mempersepsi stimulus, melainkan juga melakukan evaluasi atasnya dan
memiliki kemampuan untuk menentukan respon tertentu yang menurutnya paling efektif.
Aspek kesadaran inilah yang olesh Albert Bandura (1997) disebut sebagai agency. Berkat
agency manusia tidak hanya menerima kondisi lingkungan hidupnya sebagaimana adanya
atau semata-mata melakukan adaptasi melainkan juga mampu mengelola sumber daya untuk
memenuhi kepentingan-kepentingan hidupnya. Dalam perspektif perilaku transaksional
(Bandura, 1997; Kim & Park, 2006), manusia mampu menjalin hubungan timbal balik
dengan lingkungan hidupnya. Ia melakukan adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan
lingkungannya dan sekaligus secara kreatif mengelola sumber daya lingkungannya untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
Hubungan transaksional antara manusia dengan lingkungan ekologis menyebabkan
munculnya variasi cara berfikir dan perilaku dari satu konteks ekologis dengan konteks
ekologis lainnya (Berry & Kim, 1993). Dengan kerangka pikir tersebut, budaya kemudian
dipahami sebagai separangkat nilai kolektif yang berfungsi untuk mengkoordinasikan
perilaku semua anggota komunitas dalam rangka mencapai tujuan bersama di dalam konteks
ekologis tertentu (Kim, Hwang, & Yang, 2006). Dalam hal ini, tata nilai kultural memiliki
fungsi sebagai kerangka kerja dasar mental manusia (mental framework) (Kim & Park, 2006).
Secara lebih sederhana, cara kerja sistem nilai budaya di dalam sistem kognitif manusia dapat
diibaratkan seperti cara kerja Operating System dalam sebuah Central Processing Unit (CPU)
komputer. Meskipun di sisi lain kita juga harus menyadari bahwa proses kerja CPU ini
menjadi sangat berbeda dengan sistem kognitif manusia karena di sana tidak terdapat intensi.
Dalam perspektif perilaku transaksional tersebut, pemahaman atas proses-proses mental tidak
dapat dilepaskan dari konteks kulturalnya (Bandura, 1997). Sebuah stimulus yang sama tidak
lantas diikuti oleh respon yang sama apabila terjadi di dalam konteks yang berbeda-beda.
Sebuah stimulus obyektif berupa secarik kain merah putih akan dimaknai secara berbeda oleh
orang Indonesia dan orang Australia. Apabila Anda membakar atau menginjak-injak kain
merah putih tersebut di tengah pasar Beringharjo Yogyakarta dan dilihat oleh banyak orang
termasuk polisi, saya kira konsekuensi nasib yang akan Anda alami selanjutnyajauh lebih
tragis bila dibandingkan jika Anda melakukannya di tengah perkampungan Aborigin di
Australia. Sebuah perilaku tidak cukup hanya dipahami berdasarkan stimulus yang
mendahuluinya melainkan mengharuskan kita memahami kerangka nilai kultural individu
yang terpapar oleh stimulus tersebut.Memahami perilaku secara kontekstual inilah yang
menjadi epistimologi dalam pendekatan indigenous psychology.
Indigenous psychology sebagai bagian dari global psychology
Indigenous psychology sebenarnya bukan satu-satunya pendekatan yang menekankan
pentingnya mempertimbangkan pengaruh konteks budaya di dalam proses mental dan
perilaku. Interaksi antara pendekatan kultural dan psikologi setidaknya melahirkan tiga
perspektif dalam psikologi (Kim, 2000), yaitu perspektif universalis yang direpresentasikan
oleh psikologi lintas budaya (cross-cultural psychology, CCP), perspektif kontekstualis yang
direpresentasikan oleh psikologi kultural (cultural psychology, CP), dan, yang
terakhir,perspektif integrasionis yang diwakili oleh indigenous psychology. Untuk memahami
keunikan IP dibandingkan dua pendekatan lainnya, berikut saya akan memberikan ulasan
singkat mengenai CCP dan CP kemudian selanjutnya saya akan mencoba memberi paparan
tentang IP secara lebih detail.
1. Psikologi lintas budaya
Berry, Poortinga, Segall dan Dasen (2002) mendefinisikan psikologi lintas budaya
sebagai "the scientific study of human behavior and its transmission, taking into
account the ways in which behaviors are shaped and influenced by social and cultural
forces". Di dalam pendekatan ini, budaya diposisikan secara superfisial sebagai
sebuah variabel independen semu yang menyebabkan variasi dalam persepsi, proses-
proses kognitif, psikopatologis, kepribadian dan lain sebagainya (Kim, 2000; Kim,
Park & Park, 2000). Para psikolog lintas budaya biasanya berupaya untuk
membuktikan universalitas sebuah teori, alat ukur atau model intervensi dengan cara
menguji kecocokannya pada berbagai komunitas kultural.
Orientasi generalisasi yang ditekankan oleh pendekatan ini mendapatkan sorotan
tajam dari para kontekstualis (lihat Heinrich, Heine & Norenzayan, 2010; Shweder,
1991; Smith, Bond, & Kagitcibasi, 2006). Kim dan kolega-koleganya (Kim, 2000;
Kim, Hwang, & Yang, 2006) menilai bahwa pendekatan ini mengandung bias
Eurosentrisme yang perlu diwaspadai oleh para sarjana di luar masyarakat Barat.
Berry, dkk. (2004) secara lebih terperinci memaparkan empat level terjadinya bias
etnosentrismetersebut, yaitupada saat (i) pemilihan aitem dan stimuli dalam sebuah
instrumen, (ii) pemilihan jenis instrumen beserta prosedur penggunaannya, (iii)
definisi konsep-konsep teoritis, dan (iv) dalam pemilihan topik penelitian.
2. Psikologi budaya
Berkebalikan dengan pendekatan psikologi lintas budaya, para psikolog budaya
menggunakan perspektif kontekstualis dengan asumsi bahwa mentalitas dibentuk oleh
konteks budaya (Chiu & Chao, 2013). Hal ini mengimplikasikan pandangan dasar
mereka bahwa mentalitas sebuah komunitas kultural tertentu selalu bersifat unik dan
partikularsehingga tidak dapat diperbandingkan dengan mentalitasdari komunitas-
komunitas kultural lainnya. Shweder (1991) mendefiniskan psikologi budaya sebagai
“...the study of the way cultural traditions and social practices regulate, express, and
transform the human psyche, resulting less in psychic unity for humankind than in
ethnic divergences in mind, self, and emotion”.
Meskipun para sarjana psikologi kultural telah diakui kontribusinya dalam membawa
isu bias etnosentrisme psikologi Barat ke dalam wacana psikologi mainstream (lihat
Markus & Kitayama, 1991; Heinrich, Heine & Norenzayan, 2010), akan tetapi
mereka mendapatkan kritik tajam dalam hal pengabaiannya terhadap aspek
universalitas manusia. Kita memang bisa melihat variasi ekspresi perilaku antar
konteks budaya, akan tetapi pada lapisan yang lebih dalam kita tetap dapat
menemukan faktor-faktor universal yang melandasi variasi perilaku tersebut. Para
integrasionis memahami budaya bukan sebagai sebuah variabel independen semu
yang mempengaruhi munculnya perilaku melainkan sebagai mediator yang akan
menentukan bagaimana cara sebuah perilaku terekspresikan di dalam konteks
ekologis tertentu (Enriquez, 1993; Barkow, Cosmides, & Tooby, 1995; Kim, 2000;
Liu & Ng, 2007).
.
Bagan 1
Perspektif (A) universalisme psikologi lintas budaya, (B) kontekstualisme psikologi budaya,
dan (C) integrasionisme indigenous psychology
IP merupakan suatu pendekatan yang berupaya mengakomodasi baik aspek partikularitas
maupun aspek universalitas dari perilaku manusia (Allwood & Berry, 2010). Kim dan
kolega-koleganya (Kim & Berry, 1993; Kim, 2000; Kim, Park, & Park, 2000) mendefinisikan
IP sebagai psikologi yang berasal dari orang lokal, dikembangkan oleh orang lokal, dan
digunakan untuk kepentingan orang lokal. Walaupun orientasi IP lebih diarahkan kepada
kepentingan orang lokal, akan tetapi di sisi lain mereka juga memiliki agenda untuk
Psikologi
Global
IP 1
IP 2
IP 3
IP 4
Psikologi
kultural 1
Psikologi
kultural 3
Psikologi
kultural 2
(A) (B)
(C)
membangun psikologi global (Enriquez, 1993; Ho, 1993). Berbeda dengan universalitas ala
psikologi mainstreamyang mengandung bias etnosentris (Berry, dkk., 2004) dan terlalu
terhegemoni oleh pandangan hidup (world view) sekelompok kecil orang Barat kulit putih
kelas menengah (Heinrich, Heine & Norenzayan, 2010), psikologi global yang dicita-citakan
ini merupakan representasi akumulasi aspek kesamaan dari studi-studi IP dari berbagai
konteks budaya yang masing-masing bersifat saling melengkapi dan berada di dalam posisi
yang egaliter (Enriquez, 1993; Ho, 1993; Kim, Hwang, & Yang, 2006). Dengan pengertian
ini, psikologi mainstream yang ada sekarang akan diposisikan sebagai IP-nya orang-orang
Barat (Hwang, 2003).
Enriquez (1993) memetakan dua model indigenisasi yang umum digunakan oleh para peneliti
IP dalam mengembangkan psikologi global, yaitu indigenisasi dari jalur luar (indigenization
from without) dan indigenisasi dari jalur dalam (indigenization from within).
Indigenisasi dari jalur luar merupakan usaha indigenisasi dengan cara mengambil konsep,
teori, dan metode psikologi yang sudah ada dan memodifikasinya sehingga menjadi fit secara
kultural (Kim, 2000). Di dalam model ini, peneliti berusaha menghindari asumsi awal tentang
universalitas suatu teori sebagaimana yang umum dimiliki oleh para peneliti lintas budaya
dan menggunakan pengetahuan emic dari suatu konteks budaya untuk memodifikasi dan
mengadaptasi suatu teori. Dengan pendekatan jalur dari luar, peneliti menempatkan diri
sebagai ‘orang luar’ dan, melalui pendekatan top-down, menempatkan budaya lokal sebagai
target indigenisasi (Enriquez, 1993). Studi Cheung (2004) tentang Six Factors of Chinese
Personality Traits Theory dan Hakim (2012) tentang konsep kelekatan orangtua-anak di Jawa
merupakan dua contoh penelitian yang cukup merepresentasikan pendekatan ini.
Di sisi lain, model indigenisasi dari jalur dalam berusaha mengembangkan teori psikologi
yang berakar dari konsep-konsep, teori, dan metode penelitian yang sesuai dengan budaya
lokal (Kim, 2006; Kim, Park, & Park, 2000). Alih-alih mengimpor konsep dari luar, model
ini merekomendasikan para peneliti untuk melakukan studi eksploratori terlebih dahulu guna
mengidentifikasi dan mendefinisikan konsep-konsep psikologis lokal beserta analisis
semantiknya. Selanjutnya, peneliti akan mengembangkan konsep-konsep indigenous ini
menjadi teori-teori psikologi formal dari perspektif ‘orang dalam’ dengan pendekatan bottom-
up. Di dalam model indigenisasi dari jalur dalam ini, budaya diposisikan sebagai sumber
pengetahuan untuk melakukan indigenisasi (Enriquez, 1993). Studi Lestari (2013) merupakan
contoh yang menarik tentang bagaimana mengaplikasikan pendekatan ini dalam
pengembangan konsep psikologi Jawa rukun dalam setting kehidupan sosial.
Perbandingan dengan metode,
teknik,konsep-konsep lain, dsb.
Transfer teknologi; modernisasi
Indigenisasi dari jalur dalam
Dasar: dorongan dari dalam (indigenous)
Arah: ke luar (kultur sebagai sumber)
Indigenisasi dari jalur luar
Dasar: dorongan dari luar
(exogenous)
Arah: ke dalam (kultur sebagai
target)
Bagan 2
Konsep indigenisasi dari jalur dalam dan indigenisasi dari jalur luar (Enriquez, 1993)
Bagan 2 saya cuplik dari Enriquez (1993) untuk menggambarkan alur proses kedua model
indigenisasi dari jalur dalam dan dari jalur luar. Indigenisasi dari jalur luar diawali oleh
motivasi dari ‘orang luar’ untuk mengetahui partikularitas konstruk psikologis tertentu di
dalam suatu komunitas kultural. Proses indigenisasi diawali dari kajian eksploratif terhadap
pengetahuan-pengetahuan indigenous dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan emic
terhadap suatu konstruk kemudian menyusun ulang atau memodifikasi alat tes atau skala dan
INDIGENOUS
Asimilasi budaya, versi indigenous
dari konsep impor
Indigenisasi sebagai sebuah strategi
Indigenisasi teoritis
Indigenisasi isi, modifikasi tes, dan
penerjemahan material impor
EXOGENOUS
Identifikasi konsep-konsep kunci/
teori / metode indigenous
Elaborasi semantik
Kodifikasi atau rekodifikasi
indigenous
Aplikasi/ Penggunaan
menerjemahkan material-material impor yang relevan. Berdasarkan langkah awal tersebut
peneliti kemudian melakukan abstraksi teoritis untuk mengembangkan teori indigenous baru
atau memodifikasi teori tertentu yang sudah ada. Dengan demikian, indigenisasidari dari jalur
luar berperan sebagai sebuah strategi asimilasi kultural untuk mendapatkan versi indigenous
dari sebuah konsep psikologis yang diimpor dari luar (Enriquez, 1993; Kim, 2000)
Pendekatan indigenisasi dari jalur luar mendapatkan banyak kritik dari para psikolog
indigenous. Meskipun seorang peneliti berusaha menyingkirkan berbagai asumsi apriori nya,
bagaimanapun juga pengalaman hidup, nilai-nilai budaya asal yang menempel, dan
epistimologi yang ia bawa di dalam sistem berfikir akan turut mempengaruhi bagaimana ia
melakukan interpretasi atas temuannya (Yang, 2004; Hwang, 2005). Selain itu, Kim (2000)
juga menyoroti sisi kelemahan kompetensi cultural ‘orang luar’ untuk benar-benar bisa
menangkap budaya lokal secara utuh. Budaya bukan sekedar artefak-artefak empiris dan
sekumpulan pengetahuan yang bisa dianalisis melainkan juga sebuah pengalaman. Orang luar
mungkin bisa memahami budaya lokal akan tetapi ia tidak akan mampu menangkap aspek
pengalaman emosional dan transendental dari budaya tersebut sebagaimana yang dimiliki
oleh ‘orang dalam’ yang tumbuh dan berproses selama bertahun-tahun di dalamnya.
Di sisi lain, kehadiran peneliti dari luar juga penting dalam pengembangan IP. Orang-orang
dalam yang sudah terlalu familier dengan budayanya sendiri akan menerima budaya sebagai
sesuatu yang sudah jadi dan alamiah. Hal ini membuat mereka tidak lagi peka terhadap
keunikan-keunikan perilaku yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, Kim, Hwang, & Yang
(2006) merekomendasikan para peneliti orang dalam untuk bekerjasama dengan orang-orang
dari luar budayanya karena mereka cenderung lebih sensitif dalam menangkap kekhasan
perilaku di dalam konteks budaya yang asing baginya.
Berkebalikan dengan indigenisasi dari jalur luar, indigenisasi dari jalur dalam mensyaratkan
peneliti berasal dari komunitas budaya yang akan menjadi target penelitian. Menurut
Enriquez (1993) langkah pertama yang harus dilakukan dalam model ini adalah
mengidentifikasi konsep-konsep, teori-teori, dan metode indigenous yang dapat
dikembangkan menjadi sebuah konsep psikologi. Kesalahan yang umum dilakukan oleh para
peneliti di dalam tahap ini adalah memperlakukan konsep-konsep indigenous dan filosofis
yang terdapat di dalam teks-teks tradisional atau folklore secara langsung sebagai sebuah
teori psikologi. Padahal, sebagaimana pendapat Kim, Hwang, dan Yang (2006), konsep-
konsep ini dikembangkan sejak puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan tahun yang lalu dan
tidak dimaksudkan sebagai sebuah teori psikologi ilmiah. Tentu saja konsep-konsep ini tidak
bisa secara valid menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia modern di zaman sekarang
ini. Oleh karena itu, para pionir IP menyarankan para peneliti untuk melakukan proses
‘penerjemahan’ dari sebuah konsep filosofis menjadi konstruk psikologis. Hal ini bisa
dilakukan dengan memperjelas definisi setiap konsep terlebih dahulu, baik melalui analisis
semantik (Enriquez, 1993), refleksi filosofis (Hwang, 2005) ataupun dengan studi empiris
(Kim & Park, 1995; Yamaguchi & Ariizumi, 2006). Melalui proses penerjemahan inilah
seorang peneliti akan mampu menyusun sebuah sistem teori formal secara indigenous yang
dapat diuji kebenarannya secara ilmiah melalui serangkaian penelitian empiris.
Sekarang ini gerakan indigenisasi teori psikologi telah menjadi semangat zaman (zeitgeist)
yang membawa kemajuan signifikan di dunia psikologi Asia. Leung (2007) mencatat, kajian-
kajian indigenous psychology di berbagai negara Asia telah berhasil memberikan kontribusi
yang signifikan di dunia psikologi global. Karya-karya teoritis dari beberapa tokoh
indigenous psychology seperti Kuo-shu Yang, Kwang Kuo Hwang, dan Uichol Kim memiliki
suntingan dalam jumlah yang tinggi (high citation) tidak hanya di kalangan ilmuwan di
lingkungan budaya asalnya saja melainkan juga dari kalangan luas di luar lingkungan
budayanya. Gerakan indigenisasi juga telah berhasil menginspirasi kebangkitan intelektual
para ilmuwan psikologi di negara-negara berkembang lain baik di sesama kawasan Asia
seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand, maupun dari kawasan lain seperti Afrika, Amerika
Selatan, dan Pasifik.
Yang menarik untuk dicatat, adalah Professor Virgilio Enriquez dari Filipina yang menjadi
pionir utama dan tokoh yang berpengaruh dalam gerakan indigenisasi psikologi (Kim,
Hwang, & Yang, 2006). Akan tetapi dalam perkembangannya sekarang ini, tokoh-tokoh dan
penelitian-penelitian IP sangat didominasi oleh para ilmuwan dari negara-negara maju di
Asia Timur seperti Jepang, Korea, Cina, dan Taiwan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi
para ilmuwan bangsa Melayu di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia dan Filipina
untuk kembali bangkit dengan mengusung indigenous psychology sebagai sebuah semangat
intelektual zaman yang lahir dari dalam rahimnya.
Dimana posisi Psikologi Indonesia?
Pada titik ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda yang baru saja memutuskan
untuk memilih kuliah di jurusan psikologi, Universitas Paramadina. Saya juga ingin
mengucapkan selamat juga kepada sesama rekan akademisi muda yang baru meniti karir di
dunia akademia psikologi. Welcome to the club! Ada kabar baik yang ingin saya bagi di sini:
Psikologi Indonesia, khususnya dalam bidang riset, adalah lahan luas nan subur, dan...belum
banyak ditanami! Mengapa demikian?
Dalam sebuah tulisan menyambut satu dekade usia Association of Asian Social Psychology
(AASP), Liu dan Ng (2007) mengatakan bahwa psikologi Asia sudah mulai memiliki
identitas yang jelas dan posisi yang cukup terhormat di pentas akademia global, akan tetapi di
sisi lain masih belum mampu merepresentasikan keseluruhan atau jika tidak mayoritas wajah
psikologi Asia, terutama dari kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Perkembangan
psikologi dari Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya berbagi masalah yang
sama: belum banyak tersuarakan di outlet-outlet riset global. Laporan ini tentu saja tidak
menafikan kenyataan banyaknya program riset yang dijalankan oleh para peneliti psikologi
Indonesia. Setiap tahun lembaga-lembaga pemerintah seperti Dikti menyalurkan anggaran
yang cukup besar kepada para akademisi di Indonesia. Akan tetapi tampaknya hanya sedikit
dari riset ini yang menghasilkan artikel-artikel ilmiah yang terpublikasi secara luas, dan lebih
sedikit lagi yang terpublikasi di arena internasional, baik dalam bentuk artikel jurnal maupun
presentasi dalam kongres (lihat Tabel 1).
Tabel 1
Kehadiran Psikologi dari Negara-Negara Asia di Ajang Internasional
Negara Entri di PsycLit Partisipasi dalam kongres
Dengan kehadiran signifikan
Jepang
India
Cina
Hong Kong
Taiwan
Korea
Singapura
17217
8382
2594
1925
909
688
456
643
179
68
65
18
28
12
Kehadiran tidak terlalu
signifikan
Malaysia
Filipina
234
204
11
12
Pakistan
Thailand
Bangladesh
Indonesia
201
145
110
60
1
3
1
4
Sumber: Adair (2004)
Mengapa psikologi Indonesia belum menunjukkan kiprahnya secara signifikan di arena
internasional? Mungkin kita bisa mendapatkan jawabannya secara sekilas dari gambaran
perkembangan Psikologi Indonesia yang diuraikan oleh Prawitasari (2006). Analisis awalnya
terhadap artikel-artikel yang terpublikasi di tiga dua jurnal nasional terakreditas, yaitu Anima
dari Universitas Surabaya dan Jurnal Psikologi dari Universitas Gadjah Mada, dari tahun
2004-2005 menunjukkan sangat sedikit kajian psikologi yang menunjukkan kedekatannya
dengan konteks kultural Indonesia. Psikologi Indonesia masih belum memiliki bentuk wajah
otentiknya yang jelas dan masih bergantung pada trend penelitian psikologi di Amerika Utara
dan Eropa. Selain itu, kebanyakan penelitian bersifat studi sekali jalan (one-shot study),
biasanya menggunakan survei sebagai metode pengambilan data dengan pertimbangan paling
gampang untuk dilakukan. Tidak mudah untuk mengidentifikasi agenda riset jangka panjang
di balik penelitian-penelitian semacam ini.
Namun demikian tampaknya banyak hal telah berubah sejak Prawitasari (2006) melakukan
refleksi kritisnya terhadap psikologi Indonesia. Saya yakin dalam lima tahun terakhir ini
wajah psikologi Indonesia sudah banyak berubah. Inisiatif Fakultas Psikologi UGM atas
dorongan dari Professor Uichol Kim untuk mendirikan Center for Indigenous and Cultural
Psychology (CICP) pada akhir tahun 2009 lalu telah menghembuskan angin segar perubahan
yang membangkitkan kalangan ilmuwan di negeri kita untuk melakukan studi-studi IP.
Memang benar bahwa sebelumnya sudah ada beberapa peneliti Indonesia yang tergerak
untuk melakukan kajian-kajian psikologis berbasis konteks budaya, seperti studi Darmanto
Jatman (1991) tentang Psikologi Jawa, M. A. Subandi tentang dimensi-dimensi kultural kasus
pasien psikotik di Jawa (2006; 2008), dan Prihartanti (2004) tentang olah rasa. Akan tetapi
keberadaan CICP telah menciptakan setidaknya empat dampak positif yang meluas di
Indonesia:
Pertama adalah gerakan indigenisasi yang terprogram. Sebelumnya, penelitian IP di
Indonesia banyak dilakukan oleh individu per individu secara sporadis. Oleh karena itu,
pada saat itu perkembangan IP sangat tergantung pada kompetensi, orientasi, dan sumber
daya yang dimiliki oleh tiap individu yang tentu saja sangat bervariasi. IP bergerak
secara lambat, semangatnya menular melalui jalur hubungan-hubungan interpersonal
seperti antar pembimbing dan mahasiswa atau antar sesama peminat budaya. CICP
menawarkan strategi yang berbeda. Keberadaan peran lembaga memungkinkan
sekelompok peneliti untuk bekerjasama dan menyusun agenda dan program riset jangka
panjang yang bisa dijalankan bersama dan melibatkan lebih banyak lagi peneliti lain
serta para mahasiswa sarjana, master, dan doktoral. Strategi ini terbukti mampu
menciptakan daya dorong yang lebih besar sehingga dalam jangka waktu yang relatif
singkat, kurang lebih tiga tahun, para peneliti yang bernaung di bawah CICP berhasil
menghasilkan banyak artikel-artikel berbasis studi IP yang saling terintegrasi satu sama
lain.
Kedua adalah memperkuat perspektif internasional. Penelitian-penelitian IP pra CICP
yang diawali oleh minat pribadi si peneliti dan lebih banyak berorientasi pada
kepentingan-kepentingan lokal dan nasional. Mereka biasanya tergerak karena didasari
oleh kepedulian terhadap kelestarian kebudayaan lokal, semangat untuk
mengkontekstualisasi ajaran-ajaran tradisional di dalam kehidupan modern, dan
membebaskan diri dari cengkeraman kolonialisme teori-teori psikologi Barat. Para
peneliti di CICP masih mewarisi semangat yang sama. Akan tetapi, selain orientasi-
orientasi lokal tersebut, mereka juga memiliki keinginan kuat untuk dapat
mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian IP-nya kepada audiens yang lebih di dunia
internasional.
Indikasi adanya trend internasionalisasi para akademisi psikologi Indonesia adalah
meningkatnya keterlibatan mereka di dalam forum-forum ilmiah internasional. Sebagai
ilustrasi, di dalam forum Binneal Conference of Asian Association of Social Psychology
(BCAASP) ke-8 di India tahun 2009, jumlah peserta dari Indonesia kurang dari 50 orang
dan hanya 7 diantaranya yang mempresentasikan penelitian IP, jauh lebih sedikit
dibanding peserta dari negara-negara Asia lain seperti Jepang, India, Cina, Korea, dan
lain-lain. Akan tetapi dua tahun berikutnya ketika forum yang sama (BCAASP ke-9)
diselenggarakan di Kunming, China, jumlah peserta dari Indonesia melonjak dramatis
menjadi sebanyak 117 peserta (Liu, 2011) atau terbanyak kedua setelah tuan rumah Cina,
dan lebih dari separuhnya mempresentasikan studi IP. Geliat kemajuan Psikologi
Indonesia, khususnya yang berbasis pendekatan IP berhasil mendapatkan perhatian dunia
akademia internasional sehingga Indonesia dipercaya untuk menyelenggarakan
International Conference of Indigenous and Cultural Psychology (ICICP) yang pertama
tahun 2010 di Yogyakarta dan yang kedua pada tahun 2011 di Bali secara berturut-turut.
Kemudian tahun 2013 ini Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah untuk forum
yang lebih prestisius, yaitu BCAASP ke-10 di Yogyakarta.
Ketiga adalah mendorong kerja-kerja riset kolaboratif antar universitas. Penelitian-
penelitian IP pra CICP umumnya diselenggarakan secara individual atau sekelompok
kecil peneliti yang berasal dari lembaga yang sama. Walaupun jumlah riset kelompok ini
relatif banyak akan tetapi dalam pelaksanaannya sering kali sepenuhnya dikerjakan oleh
satu atau dua peneliti. CICP beserta cerita-cerita suksesnya ternyata kemudian
menginsipirasi kalangan akademisi psikologi Indonesia sehingga mereka tergerak untuk
membangun bekerjasama untuk mengembangkan program riset IP di institusinya
masing-masing. Sampai sejauh ini terdapat lima unit penelitian indigenous psychology
yang saling bekerjasama satu sama lain, yaitu CICP di Fakultas Psikologi UGM,
Yogyakarta; Center for Indigenous and Health Psychology (CIHP) di Prodi Psikologi
Universitas Udayana, Denpasar; Center for Indigenous and Islamic Psychology (CIIP) di
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Center for Community and
Indigenous Psychology (CCIP) Prodi Psikologi Universitas Sebelas Maret, Surakarta;
Pusat Pemberdayaan dan Pengembangan Keluarga (PPPK) Universitas Diponegoro,
Semarang; dan Unit Penelitian Indigenous Psychology UIN Syarif Kasim, Riau.
Keempat adalah mendorong keterlibatan dan pengembangan para peneliti muda. Sejak
awal pendiriannya, CICP telah melibatkan para peneliti muda terdiri dari mahasiswa
doktoral, master, dan sarjana selain tentu saja pada dosen senior dan Professor. Mereka
tidak hanya mendapatkan tugas untuk melakukan hal-hal teknis dalam pelaksanaan
penelitian, melainkan juga didorong lebih jauh untuk terlibat dalam proses analisis data,
penulisan naskah ilmiah, dan presentasi di forum-forum ilmiah nasional dan
internasional di bawah bimbingan para dosen senior dan Professor Uichol Kim sendiri.
Keterlibatan para peneliti muda ini dimungkinkan berkat visi dari Direktur CICP saat itu,
Professor Kwartarini W. Yuniarti, dan supervisor internasionalnya Professor Uichol Kim
yang berpandangan bahwa masa depan perkembangan Psikologi Indonesia berada di
tangan para peneliti generasi muda. Oleh karena itu, selain berfungsi sebagai pusat
penelitian, CICP juga memainkan peran penting sebagai kawah candradimuka guna
membangun tradisi akademik baru di Indonesia dan membentuk mentalitas dan
kompetensi akademik yang baik dalam diri para peneliti mudanya.
Sekarang ini, harapan tersebut mulai menampakkan hasilnya. Hampir seluruh pusat-
pusat studi yang saya sebutkan sebelumnya dikelola dan dimotori oleh para akademisi
muda berusia di bawah 40 tahun, yang memiliki orientasi IP yang kuat. Para akademisi
muda Indonesia yang saat aktif dalam pengembangan IP di institusinya masing-masing
antara lain David H. Tobing dan Yohannes Hendy di CHIP, Udayana; Yopina G. Pratiwi
dan Haidar B. Thontowi di CICP UGM; Moordiningsih di CIIP UMS, Moh. Abdul
Hakim dan Nugraha A. Karyanta di CCIP UNS, Dian V. S. Kaloeti dan Costrie G.
Widayanti di PPPK UNDIP, dan Mirra N. Milla di UIN Syarif Kasim Riau.
IP telah menjadi zeitgeist yang membuka peluang terciptanya kebangkitan intelektual di
kalangan peneliti psikologi di Indonesia. Mempertimbangkan bahwa kekayaan kultural
merupakan modal berharga dalam pengembangan psikologi di Asia (Kashima & Haslam,
2007; Leung, 2007), psikologi Indonesia memiliki potensi besar untuk dapat berkontribusi
secara signifikan dalam membangun psikologi global di masa depan. Sejauh ini
perkembangan Psikologi Indonesia sudah berada di dalam jalur yang benar dan cukup
menjanjikan. Akan tetapi hal ini tidak berarti kita boleh beranggapan bahwa karpet merah
telah tergelar muus di hadapan kita. Ada setumpuk pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Dalam suatu diskusi personal dengan Professor James Liu, saya mendapatkan beberapa poin
penting yang harus menjadi catatan para akademisi psikologi Indonesia. Yang pertama,
ilmuwan Psikologi Indonesia harus memiliki agenda riset jangka panjang dan program riset
yang jelas dan khas. Apa yang ingin disampaikan oleh Psikologi Indonesia kepada dunia
psikologi global? Yang kedua, Psikologi Indonesia akan berkembang baik apabila tumbuh di
tengah iklim dan tradisi akademik yang baik. Iklim akademik yang baik akan terbentuk ketika
setiap aktor yang terlibat di dalamnya memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan dan mampu bersikap terbuka untuk membangun kerjasama dan menerima kritik
dari orang lain. Yang terakhir, sebagaimana yang dinyatakan oleh para ilmuwan Asia (Leung,
2007; Kim, komunikasi pribadi; Liu & Ng, 2007), perkembangan psikologi Asa terletak di
tangan para akademisi muda. Oleh karena itu, kunci untuk membangun Psikologi Indonesia
adalah membentuk barisan generasi peneliti muda yang memiliki ambisi, komitmen, dan
kreatifitas untuk mengembangkan IP versi Indonesia sehingga nantinya dapat memberikan
kontribusi signifikan arena akademia global.
Daftar Pustaka
Allwood, C. M., & Berry, J. W. (2006). Origins and development of indigenous
psychologies: An international analysis. International Journal of Psychology, 41(4),
243-268.
Bandura, A., & Wessels, S. (1997). Self-efficacy: W.H. Freeman & Company.
Barkow, J. H., Cosmides, L., & Tooby, J. (1995). The adapted mind: Evolutionary
psychology and the generation of culture: Oxford University Press, USA.
Berry, J. W., & Kim, U. (1993). The way ahead: From indigenous psychologies to a universal
psychology. In U. Kim & J. W. Berry (Eds.), Cross-cultural research and
methodology series, Vol. 17. Indigenous psychologies: Research and experience in
cultural context (pp. 277-280). Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.
Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Segall, M. H., & Dasen, P. R. (2002). Cross-Cultural
Psychology Research and Applications (2nd ed.). Cambridge, UK Cambridge University
Chiu, C.-y., & Chao, M. M. (2013). Society, culture, and the person: Ways to personalize and
socialize cultural psychology Understanding culture (pp. 456-465): Psychology Press.
Enriquez, V. G. (1993). Developing a Filipino psychology.
Henrich, J., Heine, S. J., & Norenzayan, A. (2010). Most people are not WEIRD. Nature,
466(7302), 29.
Ho, D. Y.-F. (1993). Relational orientation in Asian social psychology.
Hwang, K.-K. (2006). Constructive Realism and Confucian Relationalism Indigenous and
cultural psychology (pp. 73-107): Springer.
Jatman, D. (1997). Psikologi Jawa: Yayasan Bentang Budaya.
Kim, U. (2000). Indigenous, cultural, and cross‐cultural psychology: A theoretical,
conceptual, and epistemological analysis. Asian Journal of Social Psychology, 3(3),
265-287.
Kim, U. E., & Berry, J. W. (1993). Indigenous psychologies: Research and experience in
cultural context: Sage Publications, Inc.
Kim, U., & Park, Y.-S. (2006). The scientific foundation of indigenous and cultural
psychology Indigenous and Cultural Psychology (pp. 27-48): Springer.
Kim, U., Yang, K.-S., & Hwang, K.-K. (2006). Contributions to indigenous and cultural
psychology Indigenous and Cultural Psychology (pp. 3-25): Springer.
Liu, J. H., & Ng, S. H. (2007). Connecting Asians in global perspective: Special Issue on past
contributions, current status and future prospects for Asian social psychology. Asian
Journal of Social Psychology, 10(1), 1-7.
Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition,
emotion, and motivation. Psychological review, 98(2), 224.
Prawitasari, J. E. (2006). Psikologi Nusantara: Kesanakah Kita Menuju? Buletin Psikologi,
14(1).
Prihartanti, N. (2004). Kepribadian sehat menurut konsep Suryomentaram. Surakarta:
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Shweder, R. A. (1991). Thinking through cultures: Expeditions in cultural psychology:
Harvard University Press.
Skinner, B. F. (1963). Operant behavior. American Psychologist, 18(8), 503.
Smith, P., & Bond, M. Kagitcibasi.(2006). Understanding social psychology across cultures:
Living and working in a changing world.
Yamaguchi, S., & Ariizumi, Y. (2006). Close interpersonal relationships among Japanese
Indigenous and cultural psychology (pp. 163-174): Springer.