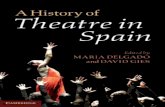Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811
Transcript of Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811
1
Raden Saleh Syarif Bustaman (sekitar 1811-1880), portret anumerta dari Mareskalek Herman Willem Daendels (menjabat, 1808-1811) yang dibuat di Den Haag 1838. Foro seizin Rijksmuseum, Amsterdam.
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 1
2
PETER CAREY
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811Hubungan Politik, Seragam dan Postweg
Daendelslezing, 22 maart 2013
Uitgeverij Vantilt / Stichting Daendels2013
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 2
3
Ik had slechts een partij te kiezen, en dit heb ik gedaan, om naamelijk vaste beginselen aan te nemen, en derzelve naar gelang der voorkomende zaken toe te passen, vooral ook om, van het eerste ogenblik af, alle voorkomende misbruiken dadelijk tegen te gaan en te verbeteren, zonder echter de zaken te vroeg uit hun geheel te brengen. (Daendels 1814, I:19)
PendahuluanMasa pemerintahan Marsekal Herman Willem Daendels sebagai
gubernur jenderal di Jawa (1808–1811) adalah titik balik dalam sejarah Indonesia modern. Bukan hanya meletakkan dasar bagi pemerintahan Hindia Belanda dan Indonesia pasca-1945 yang tersentralisasi, Daendels juga mengubah hubungan antara pemerintahkolonial di Batavia dengan para pangeran Jawa independen untuk selamanya. Ia juga memperkenalkan gaya busana dan etiket sosial baru, serta mengintegrasikan Pulau Jawa sebagai kesatuan pemerintahan dan infrastruktur baru. Baik jalan raya pos (postweg)buatannya yang terkenal itu—yang akan menjadi dasar bagi semua jalan raya trans-Jawa di masa selanjutnya—maupun reformasi administratifnya yang radikal, akan menyatukan pulau Jawa sebagai entitas koheren yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tindakan sentralisasi yang dilakukannya akan menjadi ciri khas dari setiap rezim selanjutnya di Indonesia hingga terbitnya undang-undang desentralisasi pada April 1999 di masa jabatan Presiden Habibie yang pendek (1998–1999).
Daendels diberi tugas oleh Raja Louis dari Belanda (memerintah 1806–1810) dengan kekuasaan yang begitu luas untuk mereformasi pemerintahan bekas Perusahaan Dagang Hindia Timur Belanda (VOC) yang korup (9 Februari 1807). Ia diangkat dan menduduki pangkat militer tertinggi sebagai satu-satunya marsekal dalam tentara Napoleon yang bukan orang Prancis untuk memastikan otoritas penuhnya dalam mereorganisasi pertahanan Jawa melawan Inggris. Masa jabatan Daendels selama 41 bulan sebagai penguasa kolonial tertinggi meninggalkan warisan politik yang bertahan lamadi Indonesia.
Pencarian masa kini atas “tangan besi” untuk membersihkan korupsi yang sudah menyebar luas, pencarian atas kepemimpinan yangmenentukan, dan kekuasaan negara hukum (rechtstaat)—mungkin bahkan nostalgia atas kepastian kekuasaan militer—menghubungkan penyebab ketidakpuasan di Indonesia masa kini dengan era reformasi 200 tahun lalu yang belum lama berlalu.
Daendels adalah pendatang baru di Jawa dan menjadi gubernur jenderal pertama sejak masa Laurens Reael, laksamana yang juga penyair (1583–1637, menjabat 1616–1617), yang diangkat menduduki jabatan ini dari luar lingkaran dalam organisasi VOC. Ia—sang Mareskalek Guntur atau Tuan Besar Guntur—akan mengukir namanya dalam memori kolektif orang Jawa. Tidak ada gubernur jenderal lainnya, kecuali mungkin Jan Pieterszoon Coen (1587–1629; menjabat1619–1623, 1627–1629) akan mendapatkan kehormatan seperti itu dalam masa hidupnya (Ronkel 1918; Djoko Marihandono 2013: Bab IX
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 3
4
Subbab 3, bagian 1–3).Istana dan kantor pemerintahan Daendels yang bergaya
neoklasik (imperium) di Parade Plaats (pasca-1828 Waterlooplein; pasca-1950 Lapangan Banteng) di Weltevreden—yang sekarang menjadi gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia—akan berdiri sebagai simbol dunia baru marsekal yang berani ini. Gedung ini dibangun antara 1809 dan 1828 dari batu-batu hasil pembongkaran benteng yang didirikan oleh Coen (Kasteel Batavia) dan Gereja Belanda (Hollandsche Kerk) di sebelah barat Stadhuisplein (sekarang menjadi Taman Fatahillah) (Danang Priatmodjo 2005: 11). Orang menyebutnya sebagai Witte Huis (Gedung Putih) atau l’Hotel du Gouvernement, sebutan yang lebih disukai Daendels. Gedung ini mengumumkan epos baru rasionalitas pemerintahan dan kekuasaan negara terpusat yang sama meyakinkannya dengan yang telah dilakukan oleh Banqueting House, yang dibangun oleh Inigo Jones (1619–1622), bagi London di awal masa pemerintahan Raja James I dari Inggris. Hingga saat ini, gedung ini menjadi monumen pencapaian Daendels yang mengagumkan.
Persona fiksi Daendels juga terus hidup hingga masa modern. Selama masa hidupnya sendiri, ia dikenal sebagai raja yang berani nan bijaksana yang terbebani oleh kesombongan berlebihan dan keangkuhan oleh penulis Melayu keturunan Mesir, Abdullah bin Muhammad al-Misri (1780–1820), dalam karyanya Hikayat Mareskalek (Hikayat sang Marsekal) (1813–1816 dan 1818) (Zaini Lajoubert 1987). Potret sang "Marsekal Besi" yang diromantiskan ini nantinyamuncul di awal abad ke-20.
Baik penulis Sunda, Raden Memed Sastrahadiprawira, maupun penulis Belanda, Jacques Constant van Wessem (1891–1954), akan menulis sejarah fiksi tentang dirinya. Penulis pertama memfokuskanpada perlawanan lokal terhadap postweg Daendels yang terkenal olehBupati Sumedang, Pangeran Koesoemah Dinata (1773–1828) (Sastrahadiprawira 1930). Sementara itu, penulis kedua menulis novel Boy’s own Adventure, tentang karier politik dan militer Daendels yang penuh gejolak sejak masa-masa awalnya sebagai mahasiswa hukum di Harderwijk (1781–1783) hingga kematiannya di Elmina pada Mei 1818 (Wessem 1932).
Bahkan penulis Indonesia terkenal, Pramoedya Ananta Toer (1925–2006), membahas warisan Mareskalek Guntur dan penderitaan yang disebabkan oleh pembangunan jalan raya trans-Jawa atas perintah Daendels dalam salah satu cerita pendek terakhir yang ditulisnya (Pramoedya Ananta Toer 2006).
Wawasan tentang bagaimana pandangan orang Jawa yang hidup sezaman dengan Daendels terhadap dirinya dapat ditemukan dalam catatan harian yang tidak diterbitkan yang ditulis oleh seorang bangsawan rendahan Belgia bernama Comte Edouard Errembault de Dudzeele et d’Orroir (1789–1830). Errembault pernah bertugas sebagai perwira infanteri di Jawa selatan-tengah selama Perang Jawa (1825–1830) (Errembault 1830: 17-1-1829). Saat mengomentari jalan raya pos buatan Daendels, yang dibangun dalam waktu dua tahun (1809–1810) dan membentang ribuan kilometer dari Anyer di Selat Sunda hingga Panarukan di Ujung Timur (Oosthoek), Errembaultmencatat:
On a beaucoup parlé et on parlera encore long-temps des routes que Napoléon a
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 4
5
fait faire en Europe, mais j’oserois presque affirmer qu’aucune n’a offert autant de difficultés à surmonter que celle de Buitenzorg ici [Bandung]: on ne fait que monter et descendre, environné souvent de précipices; dans de certains endroits, on a été obligé de tailler dans le roc à une profondeur considérable et de faire jouer la mine. Il falloit avoir le caractère ferme et la volonté absolue du maréchalDandels [Daendels] pour entreprendre un ouvrage de cette nature. Aucun governeur n’y avoit pensé avant lui et je crois qu’aucun n’auroit osé penser après.Les Javanais un peu instruits qui connoissent l’histoire de Napoléon, le comparent au maréchal Dandels [Daendels], en le nommant ‘le Dandels [Daendels] de l’Europe’, cependant je crois que le dernier l’emportera toujours surle premier.Banyak yang telah dikatakan—dan orang masih akan membicarakannya bertahun-tahun lagi—tentang jalan yang dibangun Napoleon di Eropa, tetapi saya berani mengatakan bahwa tidak ada satu pun yang memberikan kesulitan sangat besar seperti jalan dari Buitenzorg [Bogor] ke sini [Bandung]: tidak ada cara lain melewatinya selain naik dan turun, sering kali dikelilingi oleh jurang, di beberapa tempat mereka harus menggali ke dalam bebatuan yang cukup dalam dan menggunakan ranjau. Jalan ini memerlukan karakter yang teguh dan keinginan absolut Marsekal Daendels untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Tidak ada satu pun gubernurjenderal sebelum dia [pernah] memikirkannya dan saya yakin tidak ada satu pun setelah dia yang [juga] berani membayangkannya. Orang Jawa yang pernah mendapat sedikit pendidikan dan mengenal sejarah Napoleon akan membandingkan Napoleon dengan Marsekal Daendels, menyebut Napoleon sebagai“Daendels dari Eropa”, walaupun saya pikir ia [Daendels] akan selalu menang darinya [Napoleon].
Potret Karya Raden Saleh 1838Pada 1836–1838, seorang seniman Jawa muda, Raden Saleh
Syarif Bustaman (sekitar 1811–1880), yang baru saja menyelesaikan pendidikan magang di bidang seni selama sembilan tahun (1830–1839), diberi tugas oleh Pemerintah di Den Haag untuk melukis potret tiga gubernur jenderal,1 yang gambarnya belum dipasang secara resmi di Landsverzameling Schilderijen, galeri gubernur jenderal di Batavia (Kraus dan Vogelsang 2012:300-305).2 Salah satu gubernur jenderal ini adalah Daendels. Lukisan berjudul Gubernur Jenderal Daendels dan Jalan Raya Pos diselesaikan pada 1838. Dalamlukisan ini digambarkan Daendels, yang mengenakan seragam marsekalnya, sedang menunjuk ke peta bagian Megamendung dari postweg antara Bogor dan Cianjur di pegunungan Jawa Barat pada 1810terlihat jelas. Sebagai pintu gerbang menuju dataran tinggi Jawa Barat atau Preanger (Priangan), Megamendung adalah puncak tertinggi (1.408 meter) di sepanjang jalan raya pos ini. Lokasi ini memberikan tantangan teknik terbesar dan dikatakan memakan korban jiwa 500 buruh Jawa (Engelhard 1816: 147; Nas dan Pratiwo 2002: 710). Bahkan setelah diselesaikan, masih dibutuhkan enam ekor kerbau untuk menarik kereta kuda mendaki celah ini. Situasi ini digambarkan dalam lukisan terpisah, baik oleh Raden Saleh maupun mentornya, Antoine Auguste Joseph Payen (1792–1853) (Carey
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 5
6
2008: 198; Kraus dan Vogelsang 2012: 326-327).Tidak seperti potret dan patung kecil lainnya karya Raden
Saleh, karya tentang Daendels ini tidak dibuat secara langsung ketika sumbernya masih hidup. Karya ini didasarkan pada patung kecil yang dibuat pada 1815 oleh seniman Prancis, S.J. Rochard dandiselesaikan 20 tahun setelah kematian sang marsekal (Kraus dan Vogelsang 2012: 300). Baik patung kecil karya Rochard maupun potret karya Raden Saleh menggambarkan karakter Daendels yang teguh dan bertekad bulat. Akan tetapi, Raden Saleh menangkap “keinginan absolut” sang marsekal—menggunakan frasa Errembault—secara jauh lebih baik. Wajah Daendels dibuat dengan alis mata hitam menonjol ke luar, rahang menonjol, dan mata tanpa emosi yangmenatap ke depan. Wajah ini menggambarkan kekuasaan dan kewenangan, selain perenungan upaya yang begitu luas. Jari telunjuk tangan kiri sang marsekal yang berbalut sarung tangan kulit dan kelihatannya tidak hidup (tangan bukanlah keahlian RadenSaleh) hampir menusuk ke peta di latar depan yang menyatakan tempat, tanggal, dan pencapaian. Megamendung—‘atap dunia Jawa Barat’—ditaklukkan oleh kekuatan Eropa pasca-Revolusi.
Namun, bukan hanya penampilan dan postur Daendels yang paling menarik dari potret ini. Hal yang tidak kalah menarik adalah seragam marsekal yang dikenakannya dan tanda-tanda kehormatan yang dimilikinya. Dari lehernya tergantung pita sutra merah dan salib enamel putih Legiun Kehormatan (legion d’honneur) sementara di dadanya berkilau bintang berujung delapan dan selempang sutra biru Royal Order of Holland dari Louis Napoleon (pasca-1807 Order of the Union; pasca-1810 Order of the Reunion). Kita tahu bahwaRaden Saleh berusaha keras untuk mendapatkan semua detailnya hingga benar. Ia bahkan meminta sebuah seragam marsekal Prancis dari masa Napoleon dikirim ke Den Haag dari Paris sehingga ia bisamenempatkannya di studionya hingga ia menyelesaikan potret itu (Kraus and Vogelsang 2012: 300). Bahkan, potret ini adalah potret seragam selain potret penggunanya. Nanti, kita akan kembali membahas tema ini.
Di tangan-tangan Daendels terdapat sebuah teleskop. Ini jugasebuah detail signifikan. Sebagaimana ditunjukkan oleh seorang penulis Indonesia, Katherina Achmad (2012: 196, 205), kita mungkinmemperkirakan bahwa Daendels diperlihatkan sedang memegang tongkatkomando seorang marsekal. Namun, teleskop adalah instrumen presisi, kemahatahuan, dan jarak. Melalui instrumen seperti itulah, prestasi teknik seambisius postweg dapat dicapai. Namun, teleskop juga mengatakan tentang jarak yang jauh. Raden Saleh telah menggarisbawahi hal ini dengan adegan di sudut kiri lukisannya. Di sini, selusin sosok sangat kecil sedang bekerja keras seperti semut di bagian jalan yang terjal saat jalan tersebut berbelok menuju celah Megamendung. Bentuk badan mereka yang membungkuk hampir tidak terlihat, seperti tongkat dan anonim,benar-benar dikerdilkan oleh kemegahan pemandangan di sekelilingnya. Ini adalah para buruh pribumi yang akan mati dalam jumlah ribuan saat membuat jalan dari tanah dan batu.
Kontras antara jalinan benang emas yang mewah di seragam Daendels dengan medali dan tanda kehormatan, dan adegan pekerjaan sangat berat di latar belakang bukanlah kebetulan menurut Achmad
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 6
7
(2012:198):[…] kemegahan [seragam] Daendels memproyeksikan citra kekuatan dan kekayaan pemerintah kolonial, citra yang sangatbertolak belakang dengan penderitaan inlander [penduduk pribumi] yang dieksploitasi tanpa ampun demi kesejahteraan dan kemakmuran para penjajah. Dalam cara yang halus, Raden Saleh memberikan kepada kita sebuah ironi, menumpahkan cemooh kepada pemerintah kolonial yang hidup bersenang-senang di atas air mata, keringat dan darah orang-orang yangdijajah. Selain itu, sebuah kontras yang lebih tajam terlihat jelas […] siluet minimalis para pekerja menunjukkanbahwa pakaian mereka kotor dan compang camping. Kemegahan seragam Daendels sangat bertolak belakang dengan penampilan kumal para inlander [penduduk pribumi] yang melakukan kerja paksa untuk membangun postweg dari Anyer ke Panarukan. Tanpaharus menggambarkan para korban kerja paksa ini terbaring [mati] di pinggir jalan […] atau para pengawas membawa cambuk, kekumalan ini dengan jelas menceritakan penderitaan dan ketidakberdayaan inlander.
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 7
8
Potret Raden Saleh di Dresden pada 1841 karya pelukis Latvia, Johann Carl Ulrich Bahr (1801-1869), sekarang ada di Museum Nasional di Riga, memperlihatkan Raden Saleh sebagai seorang pangeran Timur yang mengenakan versi awal seragam 'fantasinya' (Dengan izin dari Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs [Museum Seni Nasional Latvia]).
Achmad (2012:196-197) juga mencatat signifikansi penggunaan warna yang dilakukan oleh Raden Saleh:
Dominasi warna biru pirus yang kuat dalam potret – elegan, segar dan sejuk – menunjukkan keangkuhan, kemewahan, kekuasaan dan ketenangan. Raden Saleh juga menggunakan warnaini – dalam berbagai nuansa berbeda – untuk langit, pegunungan dan selempang yang dikenakan oleh Daendels, maupun untuk pinggiran hutan lebat yang ada di ujung jalan yang baru terbangun sebagian ini. Warna biru kehijauan ini adalah motif utama dari keseluruhan komposisi dan memberikanrasa kesatuan yang kuat.
Tidak seperti anatomi manusia, penggambaran bentang alam dan penggunaan warna adalah kekuatan Raden Saleh. Sepanjang hidupnya, Raden Saleh akan berulang kali kembali ke gambar postweg. Bagian
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 8
9
Megamendung terutama mendapatkan perhatian khusus darinya (Kraus dan Vogelsang 2012: 326-335). Sebagai buktinya - ia bahkan mengetahui warna seragam merah dan putih yang dikenakan oleh kusirdi bagian ini – ia dapat melukis bagian jalan ini hanya dari ingatan dalam potret yang dibuat untuk temannya Duke Ernst II dariSaxe-Coburg dan Gotha (1818-1893, memerintah 1844-1893) pada 1876 selama kunjungan terakhirnya yang tidak membahagiakan ke Eropa (1875-1878) (Kraus and Vogelsang 2012: 332-333).
Raden Saleh menggambarkan banyak suasana di postweg yang biasanya digambarkan saat hari mulai senja ketika berkas sinar matahari yang mulai tenggelam menerangi pemandangan hutan Jawa yang luar biasa: enam orang penumpang kereta pos Hindia Timur Belanda yang ditarik oleh enam ekor lembu jantan berjuang sekuat tenaga menaiki bentangan terakhir celah itu sendiri (1862) (Kraus dan Vogelsang 2012: 326-327), warung kopi merangkap tempat pelacuran milik Ma Mina yang terkenal di dekat stasiun pos (1871) (Croockewit 1866: 326-327; Kraus dan Vogelsang 2012: 330-331), lewatnya Kereta Surat Jawa di stasiun pos di kaki celah tersebut (1876) (lihat gambar hlm. 20-21), dan kedatangan kereta kuda gubernur jenderal di stasiun pos yang sama sementara para penunggang kuda anggota pengawal pribadi Van Lansberge (1830-1903,menjabat, 1875-1881) memacu kudanya membersihkan jalan yang semakin gelap (1879) (Kraus dan Vogelsang 2012: 334-335).
Tiga tema utama potret Raden Saleh pada 1838 – hubungan politik antara pemerintah dan yang diperintah, seragam dan postweg – akan membentuk motif utama kajian kita saat ini. Kesemuanya ini pada gilirannya akan dianggap sebagai cara memahami warisan Daendels bagi Jawa.
Hubungan PolitikHampir sepertiga dari 68 pasal dalam tiga instruksi terpisah
yang diterima Daendels dari Raja Louis pada 9 Februari 1807 berkaitan dengan urusan militer dan politik. Tidaklah mengherankanjika salah satu pertimbangan strategis utama Daendels dalam merencanakan pertahanan Jawa adalah posisi keraton-keraton Jawa independen. Kekuatan dan pengaruh mereka menjadikannya pesaing potensial bagi pemerintahan Eropa dan sekutu yang meragukan jika terjadi serangan musuh. Keraton Yogyakarta merupakan ancaman yang paling ditakuti. Sumber daya militernya dan cadangan uang tunainyayang cukup besar membuatnya sangat berbahaya. Daendels sangat menyadari hal ini. Bahkan sebelum ia meninggalkan Belanda, menurutNicolaus Engelhard (1761-1831), sang marsekal ‘sudah memiliki prasangka terhadap sultan […] Ia ingin membuatnya [sang sultan] merasakan keunggulannya dan menyerangnya pada kesempatan pertama’ (Engelhard 1816: 257-258).
Walaupun pandangan Engelhard harus diterima secara hati-hatikarena posisinya sebagai pengkritik keras dan penentang sang marsekal, jelas sekali bahwa Daendels sangat ingin menempatkan hubungan antara Batavia dan keraton-keraton tersebut di atas pijakan baru. Hanya dalam waktu satu bulan setelah mulai menjabat sebagai gubernur jenderal (14 Januari 1808), ia sudah memberi tahuEngelhard tentang keinginannya untuk mendapatkan informasi
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 9
10
terperinci tentang keraton-keraton Jawa selatan-tengah. Ia juga mengatakan kepada pejabat senior VOC bahwa jabatannya sebagai Gubernur Pesisir Timur Laut Jawa akan segera diakhiri. Daendels ingin berhubungan secara langsung dengan para Residen di keraton (Daendels 1814: Bijlage 1, Organique stukken 3).
Pada 25 Februari, ia memberi taklimat kepada para Residen tentang sikap pemerintahan baru terhadap keraton (Daendels 1814: Bijlage 1, Organique wetten 6). Pasal kelima menggarisbawahi begitu pentingnya nilai yang diberikan Daendels kepada kehormatan dan gengsi pemerintahan Perancis-Belanda yang baru ini:
Mereka [para Residen] harus bersikap tenang [ongevoelige] […] untuk menampilkan kesan kekuasaan dan kemegahan pemerintah kerajaan saat ini di Belanda dan perlindungan Napoleon yang hebat, dan […] membuat mereka merasa kagum dan hormat (Daendels 1814: Bijlage 1, Organique wetten 6, article 5).
Sebelum rencana-rencana ini dapat diterapkan, baik Engelhard maupun Residen Yogyakarta yang akan mengakhiri masa jabatannya, Matthijs Waterloo (1769-1812; menjabat, 1803-1808) menanggapi permintaan Daendels atas informasi tentang keraton-keraton tersebut dengan mengusulkan kebijakan aneksasi baru yang berani.
Sementara ide-ide baru ini tentang pembagian wilayah baru bagi Jawa sedang dibicarakan, Daendels bergerak untuk menerapkan rencananya bagi hubungan baru dengan keraton. Tindakan pertamanya adalah menghapus posisi gubernur dan direktur Pesisir Timur Laut Jawa yang dilakukannya secara langsung pada 13 Mei 1808 (Haan 1910-1912, iv: 78). Sekarang, terbukalah jalan bagi komunikasi langsung antara gubernur jenderal dan para Residen. Ini adalah langkah pertama dalam rencana Daendels untuk memusatkan pemerintahan kolonial di Batavia.
Pada 28 Juli 1808, Daendels mengumumkan berlakunya Maklumat tentang Seremonial dan Etiket yang terkenal itu (Valck 1844: 140; Chijs 1895-1897, xiv: 63-65). Maklumat ini menghapuskan sebagian besar fungsi seremonial yang sebelumnya dilakukan oleh para Residen bagi para raja yang ia anggap merendahkan (Daendels 1814: 94). Sebaliknya, para Residen diberi berbagai keistimewaan yang lebih sesuai dengan posisi baru mereka sebagai perwakilan langsunggubernur jenderal dan pemerintah kerajaan Raja Louis di Den Haag.
Mereka sekarang menerima gelar ‘duta (minister)’ dengan seragam baru dan hak untuk membawa payung kenegaraan berwarna biru dan emas yang dihiasi dengan lambang kerajaan Belanda (Chijs 1895-7, xiv: 63-65). Dalam acara resmi, Residen tidak harus melepas topinya ketika mendekati seorang raja. Sebaliknya, sang raja harusberdiri untuk menyambut Residen dan langsung menyediakan tempat disebelah kiri sang raja untuk sang Residen. Hal ini akan membuat para Residen duduk tepat setingkat dengan raja. Mereka tidak lagi harus melayani sang raja dengan pekerjaan kasar yaitu menyajikan minuman dan pinang sirih. Pasal-pasal lainnya mengatur bentuk barupenghormatan kepada raja baik di dalam maupun di luar keraton. Hal terpenting adalah sang duta tidak lagi harus menghentikan kereta kudanya ketika berpapasan dengan kereta kuda raja (Carey 2008: 166).
Perubahan dalam hal seremonial menjadi perubahan paling penting bagi posisi perwakilan Belanda di keraton. Hal ini sangat
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 10
11
menyentuh jantung pemahaman orang Jawa terhadap kehadiran Belanda di Jawa. Ricklefs telah menganalisis filosofi politik Jawa ini berdasarkan tiga naskah Jawa yang berasal dari akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 (Ricklefs 1974: 362-413). Naskah-naskah ini memberi bukti bahwa pada akhir abad ke-18, keraton Yogyakarta telah melegitimasi kehadiran Belanda di Jawa Barat, kurang lebih di daerah Pasundan, dengan menganggap mereka sebagai keturunan sahkerajaan Sunda Pajajaran.
Keberadaan kerajaan ini kurang lebih sama masanya dengan keberadaan kerajaan Jawa timur yang hebat yaitu Majapahit (1292-sekitar 1527) dan memiliki sejarah yang kurang jelas. Tetapi memori tentang Pajajaran tersimpan dalam bentuk mitos dalam literatur babad Jawa modern. Bagi orang Jawa, Pajajaran memiliki dua karakteristik penting. Pertama, Pajajaran adalah kerajaan 'asing' karena berdiri di daerah Jawa barat yang menggunakan bahasa Sunda. Kedua, Pajajaran menguasai pegunungan tinggi daerah Priangan, sebuah tempat yang sangat terkait dengan pandangan orangJawa terhadap dunia makhluk halus. Nama tempat tersebut, yaitu 'Priangan', diturunkan dari kata parahyangan atau prayangan dalam bahasa Jawa yang berarti ‘kediaman makhluk halus’ (Ricklefs 1974: 375). Bentang alam ini nantinya diabadikan oleh Raden Saleh dalam lukisan-lukisannya.
Area ini memiliki kaitan penting bagi para penguasa Mataram karena pendamping spiritual mereka, Ratu Kidul, menurut tradisi keraton adalah putri Pajajaran. Tradisi yang sama mengatakan bahwaBelanda sekarang juga menjadi penerus sah kerajaan asing Pajajarandan menjadi penguasa daerah Priangan yang sangat penting secara spiritual. Legitimasi seperti ini dapat dilacak hingga pendirian Batavia oleh Gubernur Jenderal Coen pada 1619 di lokasi pelabuhan perikanan Sunda bernama Sunda Kelapa (Jayakarta). Dalam pandangan Jawa, legitimasi ini juga dapat dikaitkan dengan keturunan mitosnya dari putri Pajajaran lainnya yang membawa tanda legitimasi kerajaan dalam bentuk kelamin wanita menyala (Ricklefs 1974: 399-413; Caldwell dan Henley 2008: 165, mengutip Sahlins 2008).
Pangeran Yogyakarta, Diponegoro (1785-1855), yang nantinya akan terkenal sebagai pemimpin pasukan Jawa selama Perang Jawa (1825-1830), jelas sekali memahami tradisi ini dalam cara ini. Saat menulis dalam pengasingannya di Makassar (1833-1855), ia merefleksikan dikotomi ini antara Majapahit dan Pajajaran sebagai perwakilan dua tradisi kerajaan di Jawa dengan mengaitkan kisah dua meriam kembar yang terkenal, Kyai Setomo dan Nyai Setomi. Ia mengatakan bahwa hal ini merepresentasikan orang Belanda dan orangJawa, dengan menyatakan bahwa ‘Kota Batavia yang dikuasai Belanda telah mengambil mantel Pajajaran’ (Pajajaran wus ngalih kuthanira Batawi) (Diponegoro, ‘Makassar Notebooks’, 1838, I:155). Bagi Diponegoro dan orang-orang sezamannya, para gubernur jenderal Belanda yang dimulai dari Coen – termasuk Daendels – adalah mitra penguasa berdaulat senior di Jawa. Tetapi mereka adalah penguasa yang tidakmemiliki hak apa pun atas kerajaan-kerajaan Jawa selatan dan tengah.
Ketika Diponegoro meninggalkan Magelang menuju Batavia setelah penangkapannya oleh Jenderal Hendrik Merkus de Kock (1779-
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 11
12
1845) pada 28 Maret 1830, ia menulis dalam babad-nya bahwa ‘ia pergi meninggalkan Jawa’ (jengkarira nenggih saking Tanah Jawa) (Babad Dipanegara, IV: 187), yang menunjukkan bahwa ia menganggap dirinyasedang dalam perjalanan menuju kerajaan asing. Ekspresi praktis dari filosofi politik ini terdapat dalam pandangan orang Jawa terhadap hegemoni ganda di pulau Jawa dengan orang Belanda menguasai barat dan orang Jawa berkuasa di tengah dan timur. Hal ini nantinya juga dikenal sebagai kejawen yaitu daerah pemukiman dan pengguna bahasa Jawa.
Walaupun para penguasa Jawa selatan dan tengah merujuk gubernur jenderal Belanda dengan hormat sebagai ‘kakek’ (ingkang eyang), hal ini tidak menunjukkan hubungan pribadi yang erat. Sebaliknya, walaupun gubernur jenderal dianggap sebagai penguasa senior, ia tidak diharapkan untuk melibatkan dirinya dalam urusan keraton. Hampir semua kunjungan gubernur jenderal ke Kerajaan-Kerajaan Jawa hingga pecahnya Perang Jawa diikuti oleh masalah (RIcklefs 1974: 40, 373; Carey 2008: 168, 525-526). Gubernur jenderal baru juga diharapkan untuk menerima ucapan selamat dari sultan di ibukota kolonial, Batavia, karena hal ini memiliki sifatmisi luar negeri ke kerajaan bertetangga. Hal ini jelas sekali bukan tindakan setia dari seorang vasal kepada tuannya (Ricklefs 1974: 247- 254, 373).
Dalam situasi seperti inilah para perwakilan Belanda di keraton menduduki posisi kritis. Dalam pandangan orang Jawa, ia menjadi bagian dari dualisme yang terdiri dari dua orang, patih (perdana menteri) dan Residen yang setia kepada Belanda dan juga Jawa. Maka, para penguasa Jawa memperlakukan Residen sebagai 'dutabesar' Perusahaan Dagang Hindia Timur Belanda (VOC). Dengan demikian, ia diharuskan memenuhi fungsi-fungsi seremonial tertentudi keraton mereka. Kadang kala, Residen bahkan bertindak sebagai pelayan Raja, seperti menuangkan anggur dan menyajikan pinang sirih pada resepsi kenegaraan.
Maklumat Daendels secara efektif menghancurkan struktur politik yang diseimbangkan dengan halus yang mengizinkan kekuasaanBelanda di Jawa. Jika pasal-pasal dalam maklumat ini diterapkan, tidak ada lagi pretensi apa pun bahwa Residen merupakan 'pelayan bersama' bagi pemerintah Eropa dan raja Jawa. Reaksi kedua sang sultan, sebagaimana dicatat dalam catatan Belanda dan Jawa, adalahkecemasan. Menurut kronik keraton Yogya, ia memiliki sejumlah ilusi tentang betapa seriusnya perubahan ini (Babad Ngayogyakarta,I: 63, XVI: 42; Carey 2008: 170):
XVI 42. Sultan merasa terganggu di dalam hatinya, bersungguh-sungguh merenungkan masalah yang ada. Secara diam-diam ia sudah merasakan tentang masa depan [bahwa] Belanda akan berkuasa, mengesampingkan martabat kerajaannya [dan] mematahkan kekuasaannya.Pada akhirnya, mereka akan mengumpulkan Jawaseperti emas yang terbawa oleh air.
Dalam babad-nya sendiri, Diponegoro menyebutkan adanya diskusi yang terjadi setelah diterimanya berita tentang maklumat Daendels di Yogya. Ia menyebutkan pengaturan duduk yang baru dan hak 'duta'
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 12
13
(Residen) untuk membawa payung kenegaraan sebagai hal yang sangat menyakitkan hati (Babad Dipanegara, II: 50). Sumber Jawa lainnya memandang situasi ini sebagai menempatkan Residen setara dengan Sultan (Carey 1981: 234-235 catatan 9). Ia juga menyebutkan adanyakekhawatiran di keraton Yogyakarta ketika Daendels mengumumkan niatnya untuk mengunjungi keraton (Babad Dipanegara, II: 50):
XIV 84. […] Kemudian gubernur[-jenderal] datang ke Jawa [tengah].Namanya Jenderal Daendels.
85. Ia tiba di Surakarta[dan] ingin melanjutkan ke Yogya. Tetapi Sultan tidak menginginkannya.Karena tidak pernah ada dalam kebiasaan sebelumnyabahwa seorang gubernur[-jenderal] datang ke Jawa [selatan-tengah].Walaupun beberapa orang telah datang ke Jawa [tengah], mereka berhenti di Semarang,atau paling jauh, berhenti di Salatiga.
Secara sengaja Pangeran Diponegoro melupakan kunjungan Gubernur Jenderal Baron van Imhoff’s (1705-1750; menjabat, 1743-1750) yang berujung bencana pada Mei 1746 ke keraton Surakarta karena telah memicu pemberontakan Mangkubumi (Sultan Hamengkubuwono I, memerintah 1749-1792) – yang disebut Perang Giyanti (1746-1757) – penjelasan sang pangeran sangat sesuai dengan pandangan keraton Yogyakarta tentang pembagian Jawa menjadi dua. Dalam pembagian ini, gubernur jenderal diharapkan menetap di Batavia dan tidak melibatkan dirinya dalam urusan internal Jawa tengah.
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 13
14
Foto Raden Saleh dalam seragam 'fantasinya' oleh Woodbury dan Page di villa neo-Gothik di Cikini pada 1862. Foto seizin dari KITLV/Institut Kerajaan Belanda untuk Kajian Asia Tenggara dan Karibia.
Walaupun Diponegoro tidak menjelaskannya secara terperinci, sudah jelas bahwa reformasi Daendels sangat membuatnya gelisah. Salah satu tujuan perang yang dipimpinnya di kemudian hari adalah mengembalikan Jawa ke keadaan sebelum maklumat Daendels pada Juli 1808. Maka, dalam perundingan-perundingan gencatan senjata awal pada Desember 1829, Belanda diberi berbagai opsi yang semuanya terkait dengan masa pra-Daendels: misalnya sebagai pedagang swasta, mereka diharuskan untuk membatasi dirinya hanya di dua kota di pesisir utara, Batavia dan Semarang, dan mereka harus membayar dengan harga pasar internasional yang benar untuk barang-barang dan biaya sewa properti Jawa senilai harga pasar saat itu (Carey 1974: 285-288, 2008: 661). Pengalaman Diponegoro dengan krisis yang dipicu oleh maklumat Daendels pada 1808 telah membentuk filosofi politik jangka panjangnya. Tujuan perangnya
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 14
15
kemudian juga akan dijustifikasi oleh pengalaman Jawa selama empatdekade Tanam Paksa (1830-1870) yang pahit.
Warisan Busana Daendels: Pentingnya SeragamPemerintahan Daendels di Jawa memiliki karakter militer yang
terlihat jelas. Hal ini dapat terlihat dalam banyaknya waktu yang ia curahkan untuk masalah-masalah militer dan terutama dalam gaya busana tertentu yang ia promosikan. Tidak seperti para mantan gubernur jenderal VOC yang mengenakan busana elite kebangsawanan Belanda abad ke-18, pakaian formal Daendels adalah seragam marsekalnya.
Sumber-sumber Jawa mencatat transisi ini. Pada 29 Juli 1809,ketika Daendels tiba di Kalasan untuk memulai kunjungan resmi pertamanya selama empat hari ke ibukota Sultan, baik Diponegoro, yang menyebut Daendels sebagai ‘sang jenderal’ (lihat hlm. 16), maupun daftar kronik (sengkala) Surakarta (Carey 2008: 210), yang mencatat tentang ‘tentara’ (balatantra) – 300 kavaleri dan 300 infanteri – yang mendampingi perjalanan sang marsekal, sama-sama terkesan oleh karakter militer gubernur jenderal baru ini dan pemerintahan Perancis-Belandanya.
Penguatan pertahanan Jawa dan pembangunan tentara kolonial –yang telah diperbanyak jumlahnya oleh Daendels menjadi lebih dari dua kali lipat dari sekitar 7.000 menjadi 17.774 orang (sebagian besar direkrut secara lokal) – keduanya memiliki prioritas tinggi baginya (Peucker dan Van Hoof 1991: 57). Tetapi ia juga memperkenalkan elemen militer yang kuat ke dalam pemerintahan sipil. Onghokham (1991: 110) membandingkan Generaal Gouvernement (pemerintah jenderal [yaitu, pusat]) Daendels yang dilengkapi hirarki dependen para pejabat dengan struktur komando tersentralisasi tentara Napoleon dengan panglima tertingginya (opperbevel- hebber). Di bawah rezim baru, daerah jajahan Belanda di Jawa dibagi menjadi sembilan prefektur berdekatan, yang masing-masing dibagi kembali menjadi distrik (kabupaten) di bawah arahan bupati-nya masing-masing. Dalam kata-kata Onghokham, sang marsekal memuncaki militerisasi pemerintahan kolonial dengan memberikan pangkat militer kepada setiap pejabat, baik orang Eropa maupun orang Jawa. Mungkin, ia berharap bahwa hal ini akan menghasilkan disiplin yang lebih baik (Onghokham 1991: 110). Maka, dimulailah tradisi di dalam dinas kolonial Belanda (Binnenlands Bestuur) dan juga elite priyayi (administratif) pribumi Jawa dan Sunda pasca-Perang Jawa (1825-1830) yaitu para pejabat mengenakan 'seragam' untuk menandai status mereka sebagai pejabat sipil pemerintah yangberlanjut hingga saat ini bagi para pejabat pemerintah Indonesia (Pegawai Negeri Sipil – PNS).
Daendels juga memperkenalkan penghargaan pangkat militer tinggi dan penggunaan seragam militer bagi para bangsawan Jawa danMadura. Ia melakukannya untuk mengikat para pangeran independen ini ke rezimnya dan sebagai bentuk sistem penghargaan murah untuk menghargai kesetiaan dan jasa. Interaksi pertama Daendels dengan keraton Surakarta terjadi pada Juni 1808 ketika ia menerima
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 15
16
delegasi resmi dari keraton Sunan Surakarta di Semarang. Dalam pertemuan tersebut, salah satu tindakan pertamanya adalah menghormati putra penguasa Surakarta yang masih muda yaitu Raden Malikan Saleh, nantinya menjadi Sunan Pakubuwono VII (memerintah 1830-1858), dengan memberikan pangkat kehormatan letnan kavaleri. Putra Sunan yang masih berusia sebelas tahun ini, yang menjadi bagian dari delegasi Sunan, mendapatkan seragam ukuran anak-anak dan semua perlengkapan perwira kavaleri.Tindakan ini kelihatannya 'sangat menyentuh hati' Sunan Pakubuwono IV (memerintah 1788-1820)dan permaisurinya, Ratu Kencono, yang berasal dari Madura (Carey 2008:181).
Lukisan cat minyak karya pelukis Belgia, A.A.J. Payen (1792-1853) yang dibuat tahun 1828sesudah Payen kembali ke Eropa, berupa kereta kuda Gubernur Jenderal G.A.G.Ph. Baron van
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 16
17
der Capellen (menjabat 1816-1826) sedang ditarik oleh sebuah keruk kerbau melewati postweg Daendels di dataran tinggi Priangan di Gunung Pola dekat Sumedang, daerah yang paling susah dilewati di sepanjang jalan pos. Koleksi lukisan Payen no.200/22, Museum Volkenkunde, Leiden, Negeri Belanda.
Namun, contoh paling menarik bagi penganugerahan penghormatan militer seperti itu adalah kepada keraton Mangkunegaran. Ini adalah keluarga kerajaan Surakarta junior yang wilayah keratonnya telah diciptakan untuk Mangkunegoro pertama, Raden Mas Said (1726-1795; memerintah 1757-1795) pada akhir PerangGiyanti (1746-1757). Keraton ini memiliki tradisi ketentaraan Jawanya sendiri (Kumar 2008: 11-12, 47-48) dan dikatakan bahwa Raden Mas Said sendiri pada masa mudanya terkenal sebagai pangerankesatria. Tetapi, hubungan Daendels dengan Mangkunegoro II, Pangeran Prangwedono (1768-1835; memerintah 1796-1835; pasca-1821,
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 17
18
Mangkunegoro II), membawa dimensi baru bagi warisan militer Jawa ini.. Pada Juli 1808, ia diundang ke Semarang untuk menerima promosi sebagai kolonel penuh dalam armée Raja Belanda. Selain itu, dibentuk pula pasukan pribadinya yang berkekuatan 1.150 orangsebagai 'legiun' resmi. Legiun ini meniru Legiun Batavia milik Daendels sendiri yang tidak berumur panjang (Chijs 1895-1897, XIV:775, XV: 66; Rouffaer 1905: 603-604; Carey 2008: 182-184).
Posisi penguasa Mangkunegaran berusia 40 tahun ini sebagai 'Pangeran Kompeni' sekarang diakui secara resmi dan ia akan melayani pemerintah Eropa dengan setia hingga kematiannya pada Januari 1835. Sejak saat itu, pakaian resminya adalah seragam kolonel Eropa miliknya, rambutnya dipotong pendek sesuai gaya militer Eropa, dan gaya sosialnya adalah sebagai seorang komandan resimen yang selalu melakukan kampanye militer (Van Hogendorp 1913: 169; Carey 1992: 409 catatan 57). Hanya tutup kepalanya ataubelangkon yang tetap tersisa sebagai konsesi kecil bagi asal-usul Jawanya. Justinus van Schoor (1795-1841) yang baru berusia 27 tahun, nantinya menjadi Sekretaris Pemerintah Hindia Belanda (1830-1834) dan anggota Dewan Hindia (Raad van Indië) (1839-1841), yang mendampingi Gubernur Jenderal Van der Capellen (menjabat, 1816-1826) dalam rangkaian kunjungan resminya ke kerajaan-kerajaanJawa pada Agustus 1822, memberikan gambaran sangat jelas tentang gaya sosial Mangkunegoro II dalam buku hariannya yang diterbitkan secara anonim (Lettres de Java 1829:86): 'ia hampir tidak pernah tidur, sang pangeran dalam seragam kolonelnya tetap berdiri sepanjang malam, hanya duduk di kursinya untuk beristirahat sejenak dari waktu ke waktu’.
Penganugerahan seragam dan pangkat – Daendels akan memberikan penghormatan yang sama kepada Sultan Bangkalan pertama,Pangeran Adipati Cakraadiningrat VII (memerintah 1780-1815), dan Panembahan Sumenep, Nataningrat (memerintah 1804-1810), di Madura bagian timur – memberikan dimensi ‘Eropanisasi’ bagi etiket feodalkeraton yang merevolusi hubungan sosial di antara elite Jawa. Werner Kraus telah menangkap hal ini dengan baik dalam kajian terbarunya terhadap Raden Saleh (Kraus dan Vogelsang 2012:84):
Salah satu pertanyaan besar yang dihadapi orang-orang di dalam masyarakat kolonial […] berkaitan dengan apa yang diizinkan untuk mereka kenakan. Kode busana semi-resmi, tetapi diizinkan secara sosial, mengatakan apa yang harus dikenakan oleh penduduk daerah jajahan. Orang Tionghoa diharuskan mengenakan pakaian "nasional" mereka, yang dalam kasus para pria termasuk mengepang rambutnya di belakang kepala. Orang Jawa biasa harus mengenakan sarung dan istri mereka mengenakan sarung dan kebaya, sementara orang Jawa dari kelas sosial lebih tinggi diharuskan mengenakan jubah seremonial "tradisional" dalam panggung kolonial. Siapa pun yang berhak mengenakan seragam harus mengenakannya. Seragam Belanda termasuk hak untuk berjalan dengan tegak. Seragam Belanda tidak berlutut dan tentu saja tidak merayap di lantai. Itulah mengapa seragam sangat populer di kalangan pangeran pribumi […]. Cara bagaimana para pria ini diharuskan untuk berperilaku di muka publik tidak lagi
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 18
19
ditentukan oleh kedudukan mereka tetapi oleh pakaian mereka.
Pangeran Bernhard dari Saxe-Weimar-Eisenach (1792-1862), yang menjadi komandan tentara Hindia Timur Belanda (1847-1850), mencatat bahwa ketika ia mengunjungi keraton Sultan Paku Nataningrat (memerintah 1811-1854) di Sumenep pada akhir dekade 1840-an ia menemukan bahwa 'sekelompok pangeran anggota keluarga raja berjongkok di tanah sementara mereka yang mengenakan seragam berdiri setara dengan para tuan Eropa-nya’ (Starklof 1865-1866, i:253).
'Berdiri setara dengan para tuan Eropa-nya' secara sosial sangat diinginkan, terutama oleh mereka yang pernah mendapatkan pendidikan Eropa atau menganggap dirinya harus diperlakukan setaradengan orang Eropa. Pangeran Notokusumo (1764-1829) adalah pangeran senior Yogyakarta yang merupakan orang kepercayaan Raffles. Setelah pengangkatannya oleh Raffles sebagai pangeran independen dengan gelar Pakualam I (memerintah 1812-1829) pada 22 Juni 1812 untuk jasa-jasa yang diberikannya kepada rezim Inggris baru, ia mengadopsi gaya busana yang sama seperti Mangkunegaran, memotong pendek rambutnya dan mengenakan seragam dalam resepsi keraton (Carey 2008: 329). Hal ini memungkinkannya untuk menghindari situasi yang tidak nyaman ketika ia mungkin harus memberi penghormatan kepada sultan sebagai penguasa 'Yogya' senior. Ketika keponakannya, ayah Pangeran Diponegoro, Sultan Hamengkubuwono III (memerintah 1812-1814), diangkat sebagai sultansetelah serangan yang dilakukan Inggris terhadap keraton Yogyakarta, seragam perwira kavaleri Inggris yang dikenakan oleh Notokusumo/Pakualam I memungkinkannya untuk memberikan ucapan selamat dengan cara berjabat tangan seperti orang Eropa dan bukan harus berlutut dan menyembah secara tradisional seperti diharuskanoleh etiket keraton (Carey 2008: 356-7).
Bahkan, berkembang pandangan tentang jimat yang berkaitan dengan seragam di kalangan keraton. Sultan keempat yang masih remaja (memerintah 1814-1822), saudara muda Pangeran Diponegoro, menjadi begitu tergila-gila dengan seragam mayor jenderal Belanda yang dimilikinya dan bintang berujung delapan Order of the Union (Tanda Jasa Serikat), yang dianugerahkan Daendels kepada ayahnya pada Mei 1811, sehingga para pejabat senior di keratonnya harus bersusah payah untuk membujuknya agar ia tidak mengenakan seragam tersebut saat menghadiri upacara keraton Islam-Jawa yang paling penting, Garebeg (Carey 2008: 413, 459-460). Tak kalah menonjolnya,potret keraton resmi sang sultan memperlihatkan dirinya sedang menunggang kuda sambil mengenakan seragam militer tersebut dengan Order bertahta intan pemberian Daendels terlihat jelas (Carey 2008: 460).
Pengakuan paling menyentuh – dan mengganggu – tentang pentingnya cara berpakaian baru ala Daendels dapat ditemukan dalamsepucuk surat pribadi Raden Saleh kepada Raja Willem III (memerintah 1849-1890) yang ditulis pada 15 Maret 1865 sekitar tiga belas tahun setelah kembalinya sang pelukis ke tanah kelahirannya di Jawa (Kraus dan Vogelsang 2012: 84-5). Dalam suratini, Saleh mengajukan petisi kepada monarki Belanda untuk mengizinkannya mengenakan seragam 'fantasinya' guna menghindari
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 19
20
situasi sosial yang sangat sulit terkait dengan hubungannya dengankeraton-keraton Jawa tengah dan dalam keterlibatan dirinya dengan masyarakat Eropa kelas atas di daerah jajahan. Ia mengingatkan sang raja tentang status khususnya sebagai 'pelukis bagi raja', penghormatan yang dianugerahkan sang raja kepada dirinya pada 17 Maret 1851 tidak lama sebelum ia kembali ke Jawa. Ia kemudian melanjutkan untuk memerinci masalahnya:
[…] kesulitan aneh bermunculan di hadapannya, kesulitan yang ingin ia selesaikan karena memberikan hambatan yang cukup besar bagi pekerjaan yang ingin dilakukannya […].
Karena pendidikan Eropanya, masa tinggalnya yang lama di negara-negara pendidikan [Belanda, Jerman dan Perancis], urusannya dengan orang-orang Eropa, pelajaran-pelajaran yangtelah ditempuhnya serta seni yang telah ia ciptakan, ia tidak dapat menempatkan dirinya sendiri pada kedudukan yang sama seperti mayoritas rekan sebangsanya yang kurang berkembang, terlepas dari fakta bahwa mereka juga merupakan saudara-saudaranya.
Bahwa sebagai orang Jawa ia tidak diizinkan hadir di keraton Yogyakarta dan keraton Surakarta tanpa mengikuti adat istiadat yang ada di sana: yaitu, ia harus hadir denganmengenakan pakaian keraton, yang berarti telanjang bagian atas tubuhnya; bahwa ia tidak diizinkan untuk duduk di kursitetapi dan hanya boleh duduk di lantai sambil bersila; bahwaia harus berjalan jongkok di lantai dan banyak hal lainnya.
Bahwa, walaupun ia ingin menunjukkan rasa hormat dan penghargaannya terhadap para pangerannya, ia harus menyatakan dengan jelas bahwa sulit, bahkan tidak mungkin baginya, untuk mengikuti adat istiadat seperti itu. Bahwa rasa kesopanannya melarang dirinya untuk muncul dalam kostumkeraton Jawanya, yang kebetulan juga merusak kesehatannya, dan bahwa ia tidak dapat mengenakan tanda-tanda jasa yang dianugerahkan kepada dirinya dan bahwa hal ini saja sudah membedakan dirinya dari rekan sebangsanya.
[…] Bahwa hanya orang Jawa yang mengenakan pakaian perwira yang dikecualikan dari peraturan yang telah disebutkan di atas dan semua Radhen [Raden; gelar bangsawan rendahan] bangsawan mengenakan seragam ini. Bahwa ia bergauldengan para Pangeran dan Raden secara setara dan bahwa keistimewaan pakaian yang mereka nikmati memberikan kesulitan besar bagi dirinya.
Bahwa sudah diisyaratkan [kepadanya] beberapa kali [...] agar ia tidak perlu datang ke keraton, dan pendapat ini ingin ia bantah: 1. Bahwa jika demikian ia tidak berada dalam posisi untuk memberikan penghormatan kepada para tuannya dan bahwa hal ini akan memberikan dampak yang sangattidak menguntungkan bagi kedudukan sosialnya. 2. Bahwa ia tidak akan dapat melakukan tugas-tugasnya yang telah disebutkan sebelumnya [yaitu, melakukan kajian untuk lukisan-lukisan cat minyaknya di masa depan serta melacak objek bersejarah dan manuskrip kuno untuk kepentingan
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 20
21
Bataviaasch Genootschap] yang ada di keraton-keraton. Bahwa kesulitan-kesulitan yang telah disebutkan sebelumnya tidak hanya berkaitan dengan audiensi di keraton tetapi juga dengan semua kewajiban dan acara sosial yang tidak dapat dihadiri oleh sang pelukis.
Bahwa semua kesulitan ini akan hilang jika Yang Mulia mengizinkan penulis, dalam kapasitasnya sebagai ‘pelukis bagi raja’, untuk mengenakan seragam kapten kavaleri dalam milisi warga Batavia [schutterij] yang pernah ada. Bahwa seragam ini tidak digunakan oleh militer Belanda atau militer Hindia Belanda, hingga sama saja dengan seragam fantasi.
Bahwa ia menganggap penggunaan seragam bernilai sangattinggi, tidak hanya untuk alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi karena di luar keraton juga, semua orang yang memiliki pangkat atau gelar – dan orang-orang ini membentuk inti masyarakat Eropa di Hindia – mengenakan seragam atau kostum pada kesempatan khusus. Sementara penulis, yang tidak diizinkan untuk mengenakan pakaian Eropa di negara ini, merasa dirinya terpaksa, karenatidak adanya seragam, agar tidak sepenuhnya mengenakan pakaian Jawa dan untuk membedakan dirinya sendiri dari rekansebangsanya [yang kurang berpendidikan], untuk puas dengan semacam seragam fantasi, dan bahwa ia tidak nyaman dengan situasi ini seperti akan dipahami [dengan baik] oleh orang lain.
Maka sebagai semacam catatan tambahan di bagian akhir ia menjanjikan kepada Yang Mulia bahwa ia akan 'mengenakan seragam Milisi Batavia [Bataviaasch Schutterij] yang sekarang sudah tidak aktiflagi dengan rasa hormat dan tidak mengotorinya’, memberi tanda tangan ‘pelayanmu yang rendah dan setia – Raden Saleh’.
Petisi Raden Saleh tidak digubris. Tidak pernah ada balasan yang datang dari raja Belanda. Sebaliknya, dalam kata-kata Kraus, ‘sang pelukis terus mengenakan seragam fantasinya walaupun ia tidak menyukainya: jaket biru gelap berkancing ganda (jas tutup) […]yang kerahnya sampai ke telinganya. Seragam ini disertai dengan celana panjang biru gelap dengan setrip di samping (kadang kala iamengenakan sarung), sepatu dan penutup kepala Jawa yaitu belangkon.Sebagian pengunjung teringat akan Laksamana Nelson yang telah lamahilang dari ingatan, sementara yang lainnya menerima pakaian ini sebagai sifat eksentrik sang seniman. Namun orang menerjemahkan bahwa pakaian ini mengubah Raden Saleh menjadi makhluk setengah hati – setengah Eropa, setengah Jawa, bukan ikan atau unggas, lip-lap’ (Kraus dan Vogelsang 2012: 86).
Situasi seperti inilah yang menjadi alasan mengapa Mangkunegoro II, Pangeran Prangwedono, dengan tegas menolak semua tawaran dari Raffles (1811-1816) dan juga dari pemerintah Belanda yang kemudian kembali yaitu melalui Gubernur Jenderal Van der Capellen (menjabat, 1816-1826) untuk menyekolahkan putra-putranya di Kolkata atau Belanda karena ia takut bahwa mereka akan kembali tidak sebagai orang Eropa maupun sebagai orang Jawa (Büchler 1888,ii: 15; Carey 2008: 364).
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 21
22
Semangat yang sama – walaupun dari sudut pandang politik yang sama sekali berbeda – mendorong ketetapan hati Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa bahwa semua tawanan Belanda harus mengenakan pakaian Jawa, mempertimbangkan mengubah agamanya menjadi pemeluk Islam dan menggunakan bahasa Jawa Tinggi (krama) kepada para tawanan dan bukan bahasa negara kolonial yang tidak disukainya yaitu bahasa Melayu Pasar (Pasar Maleisch), nantinya bahasa Melayu Dinas (Dienst Maleisch) Hindia Belanda (Hoffmann 1979: 65-92; Carey 2008: 619; Kraus dan Vogelsang 2012: 60). Bentuk bahasa Melayu ini dalam pandangan Diponegoro adalah 'bahasa ayam yang tidak ingin didengar oleh penguasa di Jawa' (Carey 2008: 109). Bahasa ini nantinya menjadi topik refleksi pahit orang-orangseperti Raden Ajeng Kartini (1879-1904) pada akhir abad ke-19 ketika para pejabat Belanda bersikeras menggunakan bahasa ini saatberbicara dengan orang Jawa berpendidikan tinggi yang lancar menggunakan bahasa ibu penjajah membuat orang Jawa sangat tersinggung (Kartini 1964: 61).
Jelas sekali bahwa isu bahasa sudah menjadi topik percakapandi kalangan elite Jawa selama pemerintahan Daendels. Sebagai orangyang bukan-VOC, kemampuan berbahasa sang Marsekal tentu saja terbatas pada pengetahuannya tentang bahasa Melayu pasaran (brabbel-Maleisch). Ia tidak mengerti bahasa Jawa, bahasa elite keraton, yang dipahami oleh banyak pejabat VOC senior yang pernah bertugas di Jawa. Sebaliknya, orang-orang seperti J.G. van den Berg (1762-1842), yang pernah bertugas sebagai Residen Yogyakarta (1798-1803) dan Residen Surakarta (1803-1806), sangat menguasainya(Fasseur 1993: 66; Carey 2008: 174). Situasi ini ditunjukkan secara menarik dalam bentuk perilaku Putra Mahkota Yogyakarta, yang nantinya menjadi Sultan Hamengkubuwono III, dalam parade militer yang di selenggarakan di tempat tetirah penguasa di pedesaan atau buitenplaats (pesanggrahan) di Rojowinangun pada 1 Juni 1808. Sebagai pengganti kehadiran ayahnya, Sultan Hamengkubuwono II, yang tidak mengerti bahasa Melayu atau tidak berniat untuk menghibur orang Belanda, sang Putra Mahkota berusaha membuktikan sentimen pro-Belandanya dengan cara bersikeras bahwa tehnya harus diberi susu seperti para tamu Belanda dan berteriak sekeras-kerasnya bahwa para abdi dalem dan pejabat keraton Yogya hanya boleh berbicara dalam bahasa Melayu pada hari itu 'karena itulah bahasa yang digunakan teman Sultan, orang Belanda, dengan rakyat mereka!' (Carey 2008: 180). Dalam cara ini, perpolitikan di era Daendels mulai dimainkan dalam tingkat bahasa dan selera saat sentimen pro dan anti-Belanda memicu pembentukan faksi-faksi di keraton Yogyakarta.
Tirani Jarak:Dampak Sosial dan Kosmologi PostwegPerubahan gaya busana, bahasa dan politik yang dibawa oleh Daendels semuanya menunjuk ke arah hubungan baru antara pemerintahdan yang diperintah. Walaupun didasarkan pada pondasi militer yangrapuh, pemerintahan sang marsekal menarik garis dengan masa Kompeni sebelumnya. VOC pernah menjadi yang paling primus inter pares (pertama di antara yang setara). Namun, kedudukannya terus merosot
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 22
23
sementara kedudukan para penguasa pribumi bertambah saat kekuasaanBelanda memudar di Eropa setelah bencana angkatan laut dalam Perang Inggris-Belanda Keempat (1780-1783) dan penaklukan RepublikPerancis terhadap Belanda pada musim dingin 1794-1795. Pada 1781 dan kembali pada 1793-1794, pasukan dari sejumlah keraton diminta untuk mempertahankan ibukota kolonial dari serangan asing yang diperkirakan akan datang. Bahkan, hanya dengan kehadiran pasukan seperti itu – yang dikoordinasikan dengan baik oleh Nicolaus Engelhard yang nantinya menjadi Gubernur Pesisir Timur Laut Jawa –pendaratan Inggris di Marunda pada Oktober 1800 berhasil digagalkan (Zandvliet 1991: 79-80). Dari pangkalan angkatan laut yang penting hingga koordinasi perdagangan Belanda melalui laut dengan Timur, Jawa pada akhir abad ke-18 menjadi ‘benteng’ (bolwerk) teritorial di Samudera Hindia (Zandvliet 1991:79).
Pengangkatan Daendels mencerminkan perubahan situasi strategis ini. Postweg yang dibangunnya adalah respons imajinatifnya terhadap kenyataan militer baru: jalan ini bukan hanya memungkinkan pemindahan pasukan lewat darat – dengan demikian menghindari blokade Inggris terhadap pelabuhan-pelabuhan pesisir utara Jawa – tetapi juga berfungsi sebagai tulang punggungstrategis bagi sistem pertahanan seluruh pulau. Gerakan mundur penerus Daendels, Janssens, dari Meester Cornelis (sekarang Jatinegara di Jakarta) ke Semarang pada akhir Agustus dan awal September 1811 tidak akan mungkin dilakukan tanpa adanya jalan militer baru ini. Walaupun Daendels akan menekankan pada manfaat ekonomi dari postweg dalam surat-suratnya kepada Menteri Perdagangan dan Urusan Koloni, Paulus van der Heim (Stevens 1991:72), dan kemudian dalam pembelaannya pada 1814 terhadap pemerintahannya (Daendels 1814), sudah jelas bahwa nilai penting jalan tersebut dalam bidang militer dan strategis menduduki tempattertinggi (Nas dan Pratiwo 2002:711-712).
Keberadaan jalan tersebut menandai dimulainya Jawa modern terintegrasi dengan sistem transportasi yang membentang dari baratke timur (dan sebaiknya) di daratan menyusuri pesisir utara dan bukan, seperti sebelumnya, dari utara ke selatan (dan sebaliknya) mengikuti sungai-sungai besar yang menghubungkan pesisir dan daerah pedalaman. Nas dan Pratiwo (2002: 721) telah mengingatkan kita bahwa 'kehidupan Jawa tradisional dalam bentuk urbannya diekspresikan melalui orientasinya ke arah pegunungan dan sungai’.Mereka menyebutkan kerajaan Jawa timur besar yaitu Majapahit (1293-1527) di lembah sungai Brantas yang diamankan oleh pegunungan Anjasmoro, serta penerus Majapahit yaitu Demak, Mataramdan kota keraton Yogyakarta pasca-1755 dengan keraton-keratonnya yang diorientasikan ke arah gunung suci, Gunung Merapi (Nas dan Pratiwo 2002:721-722). Namun setelah postweg dibangun, jalan ini menggantikan sungai sebagai arteri ekonomi utama dan gagasan-gagasan kosmologis berubah secara drastis:
‘Orang-orang Tionghoa tidak lagi membangun kelenteng-kelenteng baru mereka di tepi sungai, tetapi di pinggir postweg. Mereka menganggap postweg sebagai ‘napas kehidupan’ yang baru. Kelenteng [modern] di Lasem yang dibangun pada abad ke-20 tidak lagi diorientasikan ke arah Sungai Lasem
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 23
24
seperti kelenteng lama, tetapi menghadap ke grote postweg. Perubahan yang sama terjadi dengan ‘istana’ [dalem] para bupati yang dibangun pada pertengahan abad ke-19.’ (Nas dan Pratiwo 2002: 722)
Dengan berjalannya waktu, grote postweg menjadi satu daerah urban yang sangat panjang. Bersama dengan dataran Kanto dan lengkungan sepanjang 400-kilometer antara Osaka dan Tokyo di Jepang, Jawa menjadi salah satu daerah berpenduduk paling padat di dunia. Mengutip kata-kata Nas dan Pratiwo (2002: 721), ‘kita dapat menyebut Jawa sebagai kota terpanjang di dunia dengan Grote Postweg sebagai arteri transportasi dan ekonomi utamanya’.
Tetapi hal ini telalu jauh dari cerita kita. Walaupun postweg yang masih tersisa di masa kini hampir menghilang akibat perkembangan urban Jawa, jalan tersebut pada awalnya tidak dimaksudkan seperti itu. Bahkan, penggunaan jalan trans-Jawa yang baru ini sangat dibatasi: bukan hanya karena ini adalah jalan militer, tetapi karena nama jalan tersebut sudah menyiratkan bahwajalan ini juga merupakan jalan raya pos. Pengiriman paket surat pemerintah dan personel Eropa dengan cepat adalah prioritasnya. Daendels mengorgansisasi dinas pos pemerintah yang baru dengan sekitar dua ratus kuda dan serangkaian stasiun pos untuk menggantikuda. Perubahan ini mengurangi waktu pengiriman surat antara Batavia dan Semarang dari hampir dua minggu menjadi hanya 3-4 hari(Nas dan Pratiwo 2002: 712). Mengikuti contoh Majapahit (Stutterheim 1948: 65), ia juga membentuk pasukan polisi untuk menjaga keamanan – Jayeng Sekar (polisi berkuda) yang menjadi pendahulu brigade mobil (Brimob) Indonesia masa kini (Carey 2008: 53).
Kesemuanya ini tidak murah. Errembault van Dudzeele, yang bepergian ke Batavia dari Jawa selatan-tengah dalam rangka melaksanakan cuti lokal selama Perang Jawa, memperkirakan bahwa tarif terendah sebesar 500 gulden Hindia Belanda (ƒ) untuk perjalanan darat dari Semarang ke ibukota kolonial menghabiskan biaya mendekati satu setengah kali gaji bulanannya sebagai perwiraangkatan darat berpangkat mayor infanteri (ƒ350) (Errembault 1830:19-10-1828). Setelah rute kapal uap dibuka antara dua kota ini pada 1825, menjadi jauh lebih murah untuk bepergian melalui laut: perjalanan laut selama dua hari dengan menumpang SS Van der Capellen,kapal uap pertama di Hindia Belanda yang dioperasikan oleh perusahaan Skotlandia Thompson, Robert & Co, hanya mengenakan tarif ƒ120 – termasuk makanan dan penginapan (Errembault 1830: 5-5-1826; 19-10-1828: Broeze 1979: 269; Van Enk 1999: 219 catatan 86). Dengan cara inilah Pangeran Diponegoro akan memulai perjalanan panjangnya menuju pengasingan pada awal April 1830 (Carey 2008: 586).
Daendels juga memulai sistem yang meminta para pribadi yang ingin menggunakan postweg agar terlebih dahulu menyampaikan alasanmeyakinkan untuk melakukan perjalanan tersebut. Ia juga membuat lebih sulit bagi mereka untuk mendapatkan pembiayaan bagi penggunaan kuda-kuda pos. Pada April 1865, Raden Saleh dengan cerdik mengatasi kedua masalah ini dengan cara menawarkan jasanya bagi Masyarakat Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan (Bataviaasch
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 24
25
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen) sebagai penyedia manuskrip Jawa. Masyarakat Batavia setuju untuk mengajukan permohonan perjalanan atas namanya dengan penggunaan kuda pos secara bebas dan satu bulan kemudian ia menerima izin resmi dan sponsor untuk memulai perjalanannya ke Jawa selatan-tengah (Kraus dan Vogelsang 2012: 98).
Tetapi Raden Saleh bukanlah seorang Jawa biasa. Bagi mereka yang tidak memiliki koneksi pelukis kerajaan, akses ke postweg hampir mustahil. Bahkan, jalan ini tidak dapat diakses oleh kendaraan Jawa. Jalan ini hanya diperuntukkan bagi kereta-kereta kuda Belanda lengkap dengan kusir dan para footman (pelayan laki-laki) yang diperlukan. Dalam kata-kata Krauss, 'ketika seorang petugas kolonial melakukan perjalanan di jalan ini dalam sebuah urusan resmi, tindakan tersebut bukan sekadar sebuah perjalanan, itu adalah demonstrasi kekuasaan kolonial’ (Kraus dan Vogelsang 2012: 69).
Kesan semacam itu juga dibuktikan oleh tulisan saksi mata non-Belanda pada pertengahan abad ke-19. Salah satu saksi mata tersebut adalah seorang penulis perjalanan kelahiran Stuttgart bernama Therese von Bacheracht, nantinya Therese von Lützow (1804-1852). Ia menikahi sepupunya yang saat itu menjadi komandan divisimiliter timur Jawa, Kolonel Vetter Heinrich Freiherr von Lützow (menjabat 1849-1852). Tidak lama sebelum kematiannya karena disentri di Cilacap yang terpencil dalam perjalanan pulangnya ke Jerman, ia menulis bahwa 'ketika seorang pejabat militer atau sipil berkedudukan tinggi melakukan perjalanan, hal ini dilakukan dengan pengeluaran begitu besar sehingga kelihatannya mengatakan kepada para penduduk pribumi: Kami adalah tuan dan kalian adalah pelayan!' (Therese von Lützow ‘Java Diary’ 1852, dikutip dalam Kraus dan Vogelsang 2012: 69). Pengunjung Jerman lainnya, Gustav Spieß, yang berpartisipasi dalam ekspedisi Prusia resmi pertama keAsia Timur pada 1860-1862, mengomentari bahwa ‘rasa malu [orang Jawa] di hadapan orang Eropa tak terlukiskan: setiap penunggang kuda turun dari kudanya ketika kereta kuda kami mendekat, pekerja meletakkan bebannya dan semua penduduk pribumi yang kami temui berjongkok dalam posisi rendah di tanah hingga orang kulit putih, tuwan-tuwan (para tuan kolonial), telah berkendara melewati mereka’(Spieß 1864: 400).
Maka, ‘berkendara melewati’ menjadi simbol elemen inti dalamhubungan baru antara orang Belanda dan orang Jawa yang diperkenalkan oleh postweg Daendels. Bahkan, jalan ini menjadi paradoks: pada satu tingkatan jalan ini telah memperpendek jarak fisik, pada tingkatan lainnya jalan ini telah memperkenalkan 'tirani pemisahan' baru antara pemerintah dan yang diperintah. Dalam kata-kata Kraus dan Vogelsang (2012: 69):
Sebuah kereta kuda bergerak cepat melewati jalan pos yang tertutup dan berpenerangan, dikelilingi dan dilindungi oleh para pengendara kuda dengan seragam dekoratif dan orang-orang Jawa yang berjongkok di tanah: inilah gambaran yang paling baik mencerminkan masyarakat yang mengorganisasi sistem eksploitasi kolonial yang paling berhasil [tetapi] yang bagaimana pun juga hidup di pemukiman-pemukiman dengan nama menantang dan sedikit rasa takut seperti ‘Buitenzorg’
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 25
26
(Di Luar Kesusahan) dan ‘Weltevreden’ (Puas Benar).
'Istana' Daendels. Gedung putih (witte huis) di Lapangan Waterloo (pasca-1950: Lapangan Bateng), yang sekarang menjadi gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan izin dari KITLV/Institut Kerajaan Belanda untuk Kajian Asia Tenggara dan Karibia)
Pandangan ekstrem tentang hubungan baru ini terbukti dalam novel P.A. Daum berjudul Indische menschen in Holland (Orang Hindia di Belanda) (1890):
Saya tinggal di dua kota kediaman kerajaan [Surakarta dan Yogyakarta]. Secara pribadi, saya sangat sedikit melakukan kontak dengan penduduk, dan juga tidak memiliki keinginan untuk mempelajari situasi kehidupan mereka. Saya tidak memiliki simpati sedikit pun kepada penduduk. Mereka bukanlah orang. Mereka bukan apa-apa, sama sekali bukan apa-apa. (dikutip dalam Kraus dan Vogelsang 2012: 69)
KesimpulanDirasa tidak adil untuk meletakkan tuduhan ketidakpedulian
seperti itu di kaki Daendels. Tidak seperti orang Hindia lama dalam masyarakat Den Haag pada akhir abad ke-19 yang digambarkan secara begitu jelas oleh Daum, Daendels sendiri tidak menempatkan dirinya begitu jauh di atas masyarakat pribumi. Bahkan, jika kita mempercayai bukti Nicolaus Engelhard yang bias, Daendels bahkan memiliki hubungan dengan putri Sultan Banten, Abdul Nashar Muhammad Ishaq Zainulmutaqin (sultan kedua dari terakhir yang memerintah pada 1803-1808), yang mengikutinya kembali ke Buitenzorg sebagai ‘lady-in-waiting (dayang)’ setelah ia menghapuskan kesultanan tersebut pada November 1808 (Engelhard 1816:157; Bosma dan Raben 2008:84). Tetapi warisan jangka panjang dari masa jabatannya sebagai gubernur jenderal yang bergejolak tidak dapat disangkal.
Daendels adalah seorang yang revolusioner baik dalam kontekspolitik sempit maupun dalam konteks ambisi radikalnya yang lebih luas. Ia berpikir besar. ‘Aucun governeur n’y avoit pensé avant lui et je crois qu’aucun n’auroit osé penser après’ [Tidak ada satu pun gubernur jenderal sebelum dia [pernah] memikirkannya dan saya yakin tidak ada satu pun setelah dia yang [juga] berani membayangkannya] adalah
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 26
27
rangkuman Errembault tentang keberanian Daendels membangun proyek jalan raya trans-Jawa (postweg). Ia mungkin tidak memiliki kejeniusan militer seperti Napoleon, tetapi ia setara dengan si orang kerdil Korsika dalam hal tindakan administratif. Ia tidak sedang melakukan reformasi terhadap sejumlah kecil praktik kuno, utak-atik kecil di pinggiran guna membawa Perusahaan Dagang HindiaTimur Belanda lama ke dunia modern. Ia ingin agar perubahannya mengakar dan bercabang. Pemerintahannya mengubah dunia politik Jawa. Sejak saat itu, filosofi politik Jawa yang elegan tentang dua kekuasaan berdaulat dan pembagian yang menentramkan hati antara Jawa barat/Batavia dengan Jawa – yaitu kejawèn – hampir tidak mungkin dipertahankan. Dalam segala hal yang menyentuh hubungan antara Jawa selatan-tengah dan Batavia, dari tuntutan politik pemerintahan kolonial, akses ke tenaga kerja dan sumber daya ekonomi, hingga kebutuhan militer dan pertahanan di era konflik global, sudah jelas bahwa Jawa telah memasuki zaman baru.
Sebagian sejarawan telah menilai tahun-tahun yang dihabiskanDaendels di Jawa berdasarkan sumber-sumber Eropa. Tetapi sumber-sumber tersebut terbatas. Hanya jika ia dilihat dalam konteks Jawamaka radikalismenya benar-benar terlihat. Seperti bom laut, dampakkehadirannya akan dirasakan lama setelah kepergiannya secara fisik. Banyak hal yang tidak ia rencanakan. Warisan gaya busananya– terutama warisan kode busana militer alternatifnya di keraton-keraton Jawa dan Madura – adalah produk samping pemerintahannya. Tetapi fakta bahwa seragam terus memainkan peran cukup besar dalammasyarakat Jawa adalah ukuran pengaruhnya yang luar biasa. Ia mendirikan masyarakat Jawa pada sumbunya, menawarkan cara baru untuk mendapatkan status dan rasa hormat. Sebagai gubernur jenderal pertama yang memiliki pangkat militer, ia membuat preseden yang akan bergema hingga periode modern. Di sini, ia mencerminkan tren kontemporer di Eropa: militerisasi monarki-monarki Eropa dan kecenderungan di kalangan penguasa Eropa dan keturunan prianya untuk dilukis sambil mengenakan pakaian militer (Mansel 2005).
Tentu saja, terdapat banyak sisi gelap dalam warisan Daendels: terutama tindakannya yang cepat menggunakan kekuatan danpreferensinya untuk melakukan eksekusi bergaya militer bagi orang-orang yang menggagalkan rencananya. Rezimnya di Jawa ditandai dengan tindakan kekerasan ekstrem. Sejumlah orang sezamannya bahkan menganggap ia sebagai 'monster' (Haan 1935: 557; Carey 2008: 157). Tetapi, apakah rezimnya jauh lebih kejam daripada paragubernur jenderal VOC pendahulunya atau pemerintahan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles yang menggantikannya (1811-1816) tidak perlu diperdebatkan.
Dalam hal hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, terdapat sejumlah konsekuensi jangka panjang. Sebagian konsekuensiini sudah disebutkan dalam refleksi tentang paradoks postweg: menyusutnya jarak fisik dan membesarnya jarak sosial antara para tuan kolonial dengan inlander non-elite. Bahkan pada tingkat elite,perubahan yang terjadi begitu brutal dan tiba-tiba sehingga terbukti hampir tidak mungkin bagi mereka yang tumbuh dewasa ketika orde lama Jawa masih ada, untuk membuat perubahan yang diperlukan secara sadar. Masih banyak hal yang harus terjadi
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 27
28
sebelum perubahan seperti itu dipandang sebagai kebutuhan atau tidak terhindarkan lagi. Di antara para bangsawan Jawa selatan-tengah, hanya sedikit yang mulai membuat penyesuaian yang diperlukan oleh orde kolonial baru sebelum Perang Jawa. Tetapi pada saat itu hal tersebut sudah terlambat. Waktu untuk membuat perubahan secara Jawa sudah sejak lama berlalu. Pemerintah kolonial akan melakukannya bagi mereka. Memutar jarum jam di Jawa kembali ke masa pra-Daendels, seperti yang dicoba dilakukan oleh Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa, adalah tindakan nostalgia.Setelah Daendels, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Jawa telah melewati garis tanpa titik balik menuju zaman modern.
Catatan
1 Para gubernur jenderal adalah Daendels, Van den Bosch (menjabat, 1830-1834), dan 'pelindung' Raden Saleh sendiri yaitu Jean-Chrétien Baud (menjabat, 1834-1836)
2 Potret-potret besar para gubernur jenderal – termasuk potret Daendels karyaRaden Saleh pada 1838 – di Landsverzameling Schilderijen dikembalikan ke Belanda dari Indonesia yang baru merdeka pada 27 Desember 1949 dan sekarangmenjadi bagian dari koleksi Rijksmuseum di Amsterdam. Namun, 74 salinan kecil dari potret para gubernur jenderal dan setidaknya satu lukisan lainnya dari 210 lukisan di Landsverzameling, 'Penghakiman Raja Sulaiman', tidak dikembalikan ke Belanda dan sekarang masih ada di Indonesia, komunikasi pribadi, Ir Arnoud Haag, Jakarta, 14 Maret 2013. Tentang Landsverzameling, lihat dari 210 patung kecil dan lukisan-lukisan lainnya yang berukuran lebih kecil, termasuk ‘Penghakiman Raja Sulaiman’, tidak dikembalikan ke Belanda dan sekarang masih ada di Indonesia, lihat De Loos Haaxman, ‘De verzameling ’s-Lands schilderijen. Ontstaan, groei en restauratie’, Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap, 80 (1940), 367-84.
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 28
29
Daftar Pustaka
Achmad, Katherina 2012 Kiprah, Karya, dan Misteri Kehidupan Raden Saleh: Perlawanan Simbolik Seorang Inlander. Jakarta: Narasi.
Babad Dipanegara 2010 Babad Dipanegara. 4 vol, ed. Nindya Noegraha. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Babad Ngayogyakarta 1876 Babad Ngayogyakarta. Sana Budaya mss. A135 A136, A144, 3 vol, dikompilasikan di Yogyakarta oleh Pangeran Suryonegoro (1822-86) dan RadenAdipati Danurejo v (1810-?1885).
Bosma, Ulbe and Remco Raben 2008 Being “Dutch” in the Indies. A History of Creolisation and Empire, 1500-1920. Singapore: NUS Press.
Broeze, F.J.A. 1979 ‘The Merchant Fleet of Java 1820-1850; A preliminary survey', Archipel 18: 251-269.
Büchler, A.P. 1888 ‘Soerakarta vóór 63 jaren’, Tijdschrift van Nederlandsch-Indië (TNI) 17-1:401-431, 17-2:1-38.
Caldwell, I. dan D. Henley 2008 ‘The Stranger who would be King; Magic, Logic, Polemic’ dalam: I. Caldwell dan D. Henley (ed). ‘Stranger Kings in Indonesia and Beyond’, Indonesia and the Malay World, 36: 159-324.
Carey, Peter 1974 ‘Javanese Histories of Dipanagara: The Buku Kedhung Kebo, its authorship and historical importance’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 130: 259-88.
Carey, Peter 1981 Babad Dipanagara; An Account of the Outbreak of the Java War (1825-30); The Surakarta Court Version of the Babad Dipanagara with Translations into English and Indonesian Malay. Kuala Lumpur: Art Printers.
Carey, Peter 1992 The British in Java, 1811-1816; A Javanese Account. Oxford: Oxford UniversityPress.
Carey, Peter 2008 The Power of Prophecy; Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855. Leiden: KITLV Press.
Chijs, J.A. van der 1895-97 Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602-1811. Vol. XIV(1807-1808), XV (1808-1809), XVI (1810-1811). ’s-Gravenhage: Nijhoff.Croockewit, A.E. 1866 ‘Zes Weken in de Preangerschappen’, De Gids, Jaargang 30, hlm.
290-328.Danang Priatmodjo (ed.) 2005 Ministry of Finance Building: The White House of Weltevreden.
Jakarta: Pusat Dokumentasi Arsitektur.Daendels, H.W. 1814 Staat der Nederlandsche Oostindische Bezittingen, onder het Bestuur van den
Gouverneur-Generaal Herman Willem Daendels, ridder, luitenant-generaal &c. in de Jaren 1808-1811. ’s-Gravenhage: Van Cleef.
Daum, P.A. (pseud. Maurits) 1890 Indische Mensen in Holland: oorspronkelijke roman. Leiden: Sijthoff.
Diponegoro, Pangeran 1838 ‘Makassar Notebooks’, Fort Rotterdam, Makassar, fotokopiperpustakaan dari manuskrip yang sebelumnya dimiliki oleh almarhum Raden Mas Jusuf Diponegoro dan almarhum Raden Mas Saleh Diponegoro, Jalan Irian no. 83, Makassar. 2 volume.
Djoko Marihandono 2013 Centralisme Pemerintahan: Herman Willem Daendels di Jawa, 1808-1811:Penerapan Instruksi Napoléon Bonaparte Jakarta: Kommunitas Bambu.
Engelhard, N. 1816 Overzigt van den Staat der Nederlandsche Oost-Indische Bezittingen onder hetBestuur van den Gouverneur-Generaal Herman Willem Daendels enz. enz. ’s-Gravenhage,Amsterdam: Van Cleef.
Enk, E.M.C. van 1999 Britse kooplieden en de cultures op Java; Harvey Thomson (1790-1837) en zijn financiers. Leiden: Grafaria.
Errembault de Dudzeele et d’Orroir, Comte Edouard 1825-30 ‘Journal’ [Catatan Harian Kampanye Perang Jawa, 22 Oktober 1825 – 25 Mei 1830], efeo 58653, manuskrip École Française d’Extrême Orient, Paris.
Fasseur, C. 1993 De Indologen; Ambtenaren voor de Oost, 1825-1950. Amsterdam: Bert Bakker.Haan, F. de 1910-12 Priangan; De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811.
Batavia, ’s-Gravenhage: Landsdrukkerij. Empat volume.Haan, F. de 1935 ‘Personalia der periode van het Engelsch bestuur over Java, 1811-
1816’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 92: 477-681.Hogendorp, H. Graaf van 1913 Willem van Hogendorp in Nederlandsch-Indië 1825-1830. ‘s-
Gravenhage: Nijhoff. Hoffman, J. 1979 ‘A oreign Investment; Indies Malay to 1901’, Indonesia 27:65-92.Kartini, Raden Adjeng 1964 Raden Adjeng Kartini; Letters of a Javanese Princess. New York:
Norton.Kraus, Werner dan Irina Vogelsang 2012 Raden Saleh. The Beginning of Modern Indonesian
Painting. Jakarta: Goethe Institut.
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 29
30
Kumar, Ann 2008 Prajurit Perempuan Jawa: Kesaksian Ihwal Istana dan Politik Jawa Akhir Abad Ke-18. Jakarta: Kommunitas Bambu [Judul asli: ‘Javanese Court Society and Politics in the Late Eighteenth Century: The Records of a Lady Soldier. Part I: The Religious, Social and Economic Life of the Court’, Indonesia no. 29 (April 1980):1-46; ‘Part II: Political Developments: The Court and the Company, 1784-1791’, Indonesia no. 30 (Oktober 1980): 67-111].
Lettres de Java 1829 Lettres de Java ou Journal d’un Voyage en cette Île, en 1822. Paris: n.p. [nama samaran pengarang J. van Schoor.]
Lützow, Therese von 1852 ‘Javanischen Tagebuch’. Nachlass Lützow, Staatsbibliothek(sbsp) zu Berlin, Handschriftenabteilung.
Mansel, Philip 2005 Dressed to Rule; Royal and Court Costume from Louis XIV to Elizabeth II. New Haven: Yale.
Nas, Peter J.M. dan Pratiwo 2002 ‘Java and de groote postweg, la grande route, thegreat mail road, Jalan Raya Pos’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 158: 707-725.
Onghokham 1991 ‘Daendels en de vorming van het koloniale en moderne Indonesië’, dalam F. van Aanrooy dkk, Herman Willem Daendels 1762-1818. Geldersman-patriot-Jacobijn-generaal-hereboer-maarschalk-Gouverneur, van Hattem naar St George del Mina. Utrecht: Matrijs: 107-114.
Peucker, P.M. dan J.P.C.M. van Hoof 1991 ‘Daendels, een groot generaal?’ dalam F. van Aanrooy dkk, Herman Willem Daendels 1762-1818. Geldersman-patriot-Jacobijn-generaal-hereboer-maarschalk-Gouverneur, van Hattem naar St George del Mina. Utrecht: Matrijs: 47-60.
Pramoedya Ananta Toer 2006 Jalan Raya Pos, Jalan Daendels. Jakarta: Lentera Dipantara.Ricklefs, M.C. 1974 Jogjakarta under Sultan Mangkubumi, 1749-1792; A History of the Division of Java.
Oxford: Oxford University Press.Ronkel, Ph.S. van 1918 ‘Daendels in de Maleische literatuur’, Koloniaal Tijdschrift 7:
858-875.Rouffaer, G.P. 1905. ‘Vorstenlanden’, Encylopaedie van Nederlandsch-Indië 4: 587-653.Sahlins, Marshall 2008 ‘The Stranger King’, dalam: I. Caldwell dan D. Henley (ed).
‘Stranger Kings in Indonesia and Beyond’, Indonesia and the Malay World, 36: 177-199.Sastrahadiprawira, Raden Memed 1930 Pangeran Kornel. Diterjemahkan oleh Abdoel Moeis.
Weltevreden: Balai Pustaka.Spieß, Gustav 1864 Die Preußische Expedition nach Ostasien während der Jahre 1860-62: Reise-Skizzen
aus Japan, China, Siam und der Indischen Inselwelt. Berlin: Spamer.Starklof, R. 1865-66 Das Leben des Herzogs Bernhard von Sachsen-Weimar-Eise-nach, koniglich
Niederlandischer General der Infanterie. 2 volume. Gotha: Thienemann.Stevens, Th. 1991 ‘De Postweg van Daendels: Een vraagstuk’, dalam F. van Aanrooy
dkk, Herman Willem Daendels 1762-1818. Geldersman-patriot-Jacobijn-generaal-hereboer-maarschalk-Gouverneur, van Hattem naar St George del Mina. Utrecht: Matrijs: 71-76.
Stutterheim, W.F. 1948 De kraton van Majapahit, ’s-Gravenhage: Nijhoff. [KITLV Verhandelingen 7]
Valck, F.G. 1844 ‘Overzigt van de Voornaamste Gebeurtenissen in het Djocjocartasche rijk, sedert dezelfs Stichting (1755) tot aan het Einde van hetEngelsche Tusschen-Bestuur in 1816’, ed. J.C. Steyn Parvé, Tijdschrift voor Ned- erlandsch Indië, 6-3: 122-157, 262-288; 6-4: 25-49.
Wessem, J.C. van 1932 De IJzeren Maarschalk: Het Leven van Daendels, “soldat de fortune”; roman. Amsterdam: De Spieghel; Mechelen: Kompas.
Zaini-Lajoubert, Monique 1987 Hikayat Mareskalk. Bandung: Angkasa Zandvliet, K. 1991 ‘Daendels en de nieuwe kaart van Java’, dalam F. van Aanrooy dkk, Herman Willem Daendels 1762-1818. Geldersman-pariot-Jacobijn-generaal-hereboer-maarschalk-Gouverneur, van Hattem naar St George del Mina. Utrecht: Matrijs: 77-105.
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 30
31
Desain sampul: Mijke Wondergem, Baarn Book design: Martien Frijns,Doetinchem
ISBN 978 94 6004 142 6
© 2013, Peter Carey, Serpong-BSD & Uitgeverij Vantilt, Nijmegen
Gambar sampul: Raden Sarief Bustaman Saleh, ‘Posthuum portret van Herman Willem Daendels (1762-1818).Gouverneur-generaal (1808-10)’, 1838. © Rijksmuseum, Amsterdam.
Publikasi ini sama sekali tidak boleh diperbanyak dan/atau disebarluaskan dalam bentuk cetakan, fotokopi, mikrofilm atau bentuk lainnya tanpa seizin penerbit.
Telah dilakukan semua upaya untuk melacak pemegang hak cipta dan mendapatkan izin merekauntuk menggunakan bahan yang memiliki hak cipta sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penerbit meminta maaf jika terdapat kesalahan atau kelalaian dan sangat berterima kasih jika mendapatkan informasi tentang koreksi apa pun.
Daendels dan Ruang Suci Jawa, 1808-1811 Page 31