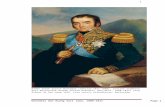METHAREZQI SUCI ARSIH-FKIK.pdf - Institutional Repository ...
konsep, kitab suci, dan relevansinya dengan budaya lokal
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
Transcript of konsep, kitab suci, dan relevansinya dengan budaya lokal
AGAMA HINDU
KONSEP, KITAB SUCI, DAN RELEVANSINYA DENGAN BUDAYA LOKAL
Oleh
I Wayan Latra, S.Ag,M.Si.
NIP 195812311981031049
UPT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA
UNIVERSITAS UDAYANA
2019
i
KATA PENGANTAR
Oý Swastyastu
Puji syukur peneliti panjatkan ke hadapan Sang Hyang Widhi/Tuhan
Yang Mahaesa atas rahmat yang dilimpahkan sehingga penelitian yang
berjudul “Agama Hindu Konsep, Kitab Suci, dan Relevansinya Dengan
Budaya Lokal” dapat diselesaikan. Dalam pelaksanaan penelitian ini tidak
sedikit hambatan yang dihadapi, namun berkat karunia-Nya akhirnya segala
rintangan tersebut dapat diatasi.
Keberhasilan penelitian ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu
saya sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang
telah membantu hingga selesainya tulisan ini.
Disadari sepenuhnya atas keterbatasan pengetahuan dan kemampuan
yang dimiliki sehingga karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Untuk hal itu
diharapkan masukan, kritik, dan saran dalam penyempurnaannya, serta untuk
menambah wawasan dan cakrawala pengetahuan peneliti.
Akhirnya atas segala bantuan Bapak/Ibu/Sdr., peneliti doakan semoga
mendapat pahala yang berlipat dari Tuha Yang Mahaesa.
Oý Úàntiá, Úàntiá, Úàntiá, Oý
Denpasar, Januari 2019
Peneliti,
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR …………………………………………………………….
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………
i
ii
I PENDAHULUAN……….……………………………………………………… 1
1.1 Latar Belakang ………...……………………………………………..
1.2 Masalah ……………...…………………………………………….….
1.3 Tujuan ………………………..………………………………………..
1
4
4
II AGAMA HINDU: KONSEP, KITAB SUCI, DAN RELEVANSINYA
DENGAN BUDAYA LOKAL ………………………………………………...
4
2.1 Konsep Agama Hindu ……………………...………………………..
2.2.Veda Sebagai Kitab Suci Agama Hindu ……………………...…..
2.2.1 Kelompok Veda Sruti ……………………...………………………
2.2.2 Kelompok Veda Smrti …………………………………………….
2.3 Kerangka Dasar Agama Hindu dan Relevansinya Dengan
Budaya Lokal …………………………………………………………
4
10
12
19
23
III SIMPULAN ………………...……………………………………..………….. 28
IV KEPUSTAKAAN ……………………………………………………………. 30
1
AGAMA HINDU:
KONSEP, KITAB SUCI, DAN RELEVANSINYA DENGAN BUDAYA LOKAL
I PENDAHULUAN
Tiap Agama di dunia ini, memiliki pustaka/kitab suci. Pustaka suci
sebuah agama menjadi sumber segala sumber ajaran agama tersebut. Aspek-
aspek filsafat, aspek ritual maupun etika pelaksanaan ajaran beragama,
bersumber dari nilai, kaedah, norma dari pustaka sucinya. Semua ajaran
agama ini memiliki kebenaran suci, kekal dan universal sehingga patut diikuti
dan dilaksanakan oleh penganutnya.
Weda kitab suci sumber ajaran Hindu, satu-satunya secara tradisional
kita miliki yang mengatakan bahwa weda adalah kitab suci agama Hindu.
Sebagai kitab suci agama Hindu maka ajaran Weda diyakini dan dipedomani
oleh umat Hindu sebagai satu-satunya sumber bimbingan dan informasi yang
diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ataupun untuk waktu-waktu tertentu.
Diyakini sebagai kitab suci karena sifat isinya dan yang menurunkan
(mewahyukan) adalah Tuhan Yang Maha Esa yang Maha Suci. Apapun yang
diturunkan sebagai ajaran-Nya kepada umat manusia adalah ajaran suci
terlebih lagi bahwa isinya itu memberikan petunjuk atau ajaran untuk hidup
suci.
1.1 Latar Belakang
Manusia bukan hanya elemen dari sistem sosial, akan tetapi menyatu
dengan lingkungan alam, yakni panggung, lokalitas atau ruang tempat mereka
beraktivitas. Aktivitas mereka tidak bersifat acak, melainkan berpola karena
2
mereka memiliki kebudayaan yang di dalamnya mencakup pengetahuan,
gagasan, nilai, norma, ideologi, kepercayaan dan agama (Geertz, 1973,
Spradley, 1972 dalam Atmaja, 2004:1). Terintegrasinya setiap elemen dalam
kebudayaan tersebut menimbulkan suatu interaksi yang saling komplementer.
Eksistensi ini dalam suatu komunitas yang dinamis setidaknya dapat
mewujudkan sistem kesetimbangan antar komponenen dalam subsistem
kebudayaan tersebut.
Salah satu aspek yang menonjol yang perlu diperhatikan dalam
kaitannya dengan upaya meredam munculnya maslah-maslah sosial adalah
pengamalan ajaran agama. Dengan pengamalan ajaran agama yang dianut
secara mantap dalam perilaku kehidupan sehari-hari baik sebagai individu,
dalam keanggotaan keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat, bangsa
dan Negara. Dan jika melihat akar budaya bangsa Indonesia pada prinsipnya
pola kerukunan kehidupan beragama baik intern maupun antara umat
beragama tertanam sangat kokoh yang merupakan jati diri kepribadian bangsa
di mata bangsa-bangsa lain di muka planet bumi ini.
Pada tingkatan yang paling pribadi pengamalan ajaran agama
memberikan suatu fungsi membantu manusia memanusiakan dirinya. Dalam
arti pada tingkat ini ajaran agama dapat digunakan sebagai pedoman hidupnya
serta memformulasikan tujuan-tujuan hidupnya baik sifatnya dalam aspek
jasmaniah maupun dalam aspek rohaniah. Dengan memiliki suatu bentuk
keyakinan yang mantap mereka mampu bertahan hidup sekalipun dalam
kondisi yang kritis.
3
Dalam hubungannya dengan individu lain di tengah-tengah masyarakat,
guna membantu manusia menetapkan peran dan tanggungjawabnya sebagai
suatu anggota keluarga manusia. Salah satu yang utama ditawarkan oleh
agama-agama kepada manusia adalah kedamaian. Kedamian dengan diri
sendiri, kedamaian dengan orang lain, kedamaian dalam masyarakat,
kedamaian di dunia ini, bahkan kedamaian di akhirat (Gunadha, 2001:2).
Konsep kedamaian ini yang dalam orientasi kepentingan nasional jika betul-
betul diterapkan dalam perilaku kehidupan beragama diharapkan mampu
memciptakan kerukunan hidup.
Namun ketika persoalan, antara lain manakala orang sulit membedakan
antara agama yang diberi peran sebagai “jalan” menuju “tujuan”, dan agama
sebagai tujuan. Dalam pengertian ini, perbedaan bukanlah sesuatu yang aneh.
Karena itu tidak seharusnya perbedaan menyebabkan orang bermusuhan.
Ketika agama menjadi satu-satunya dan segala-galanya, di sinilah yang
menjadi masalah, karena tidak ada ruang bagi orang lain. Apa pun yang ada di
sekitarnya dipandang sebagai ancaman, saingan (Sarapung, 2001:xix).
Fenomena tersebut memiliki tendensi memunculkan gerakan sosial
keagamaan yang berupaya mengadakan suatu perubahan yang dilandasi oleh
kepentingan-kepentingan tertentu.
1.2 Rumusan Masalah
a. Bagaimana Konsep Ajaran Dalam Agama Hindu?
b. Bagaiman Veda Sebagai Kitab Suci Agama Hindu?
c. Bagaimana Kerangka Dasar Agama Hindu dan Relevansinya dengan
Kebudayaan Lokal?
4
1.3 Tujuan
a. Untuk mengetahui Konsep Ajaran Dalam Agama Hindu
b. Untuk mengetahui Veda Sebagai Kitab Suci Agama Hindu
c. Untuk memahami Kerangka Dasar Agama Hindu dan Relevansinya
dengan Kebudayaan Lokal
II. AGAMA HINDU: KONSEP, KITAB SUCI, DAN RELEVANSINYA
DENGAN BUDAYA LOKAL.
2.1 Konsep Agama Hindu
Sebelum diuraikan secara lebih mengkhusus tentang pengertian Agama
Hindu, maka terlebih dahulu diuraikan mengenai pengertian agama secara
deskripsi umum dari beberapa ahli. Jika meminjam pemikiran ahli-ahli dari
barat, menurut Emile Durkheim, agama merupakan seperangkat keyakinan
dan praktek-praktek yang berkaitan dengan yang sakral, yang menciptakan
ikatan sosial antar individu (Turner, 2012:22). Menurut Clifford Geertz
menyatakan bahwa agama adalah: (1) sebuah sistem simbol yang berperan,
(2) membangun suasana hati dan motovasi yang kuat, pervasive, dan tahan
lama di dalam diri manusia dengan cara (3) merumuskan konsepsi tatanan
kehidupan yang umum dan (4) membungkus konsepsi-konsepsi ini dengan
suatu aura faktualitas semacam itu, sehingga, (5) suasana hati dan motivasi
tampak realitik secara unik (Pals, 2001:414).
Menurut Nasution (dalam Jalaludin, 2010:12), intisari dari pemahaman
mengenai definisi agama adalah adanya ikatan. Karena itu agama
mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan
5
yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia
sebagai kekuatan gaib tang tak dapat ditangkap dengan panca indera, namun
mempunyai pengaruh besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari.
Agama sendiri pada hakikatnya merupakan suatu kepercayaan atau
keyakinan melalui ajaran-ajarannya yang bersumber dari wahyu (sabda suci)
Tuhan Yang Maha Esa tentang mengadakan hubungan, baik antara manusia
dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, maupun manusia dengan
alamnya. Istilah agama sendiri jika dilihat secara etimologis berasal dari bahasa
Sanskerta. Kata agama berasal dari akar kata “a” dan “gam”. Akar kata “a”
berarti tidak dan “gam” berarti pergi. Identik dengan kata “go” dalam bahasa
Inggris. Jadi agama berarti tidak pergi, diam di tempat, langgeng diwariskan
secara turun temurun (Siwananda, 2003:1; Ngurah Nala, 1993:4). Sedangkan
kata Hindu pada awalnya merujuk pada sebuah peradaban yang terdapat di
lembah Sungai Indus. Kata itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta “Shindu”,
yang oleh bangsa Persia kuno diucapkan sebagai “Hindu” (Keene, 2010:10).
Di Barat (Inggeris, Perancis, Jermal dll) agama ini diterjemahkan dengan
kata religion yang bersal dari kata Yunani, yaitu relegere. “re” berarti kembali,
sedangkan “legere” mengandung makna mengikat. Jadi relegere adalah
mengikat kembali agar diam atau tidak bergerak. Siapa atau apa yang diikat
kembali? Tentu yang dimaksudkan di sini adalah manusia agar kembali
mengikatkan dirinya dengan Tuhan sebagai asalnya, yang maha kekal dan
abadi. Dengan jalan mengikatkan diri kembali kepada-Nya, maka manusia
menemukan dirinya, menemukan kebahagiaan dan kebenaran. Di dalam
6
ajaran agama inilah diketemukan cara-cara bagaimana agar kita dapat
menyatu kembali dengan-Nya (Ngurah Nala, 1993:4).
Di dalam lontar Sundarigama, kata agama dikupas dan diberi pengertian
sebagai beriku:
Agama. Kata agama ini terdiri dari suku kata a, ga, dan ma, masing-masing
suku kata ini mempunyai makna sendiri-sendiri. A berarti awang-awang
atau kosong atau hampa; Ga mengandung pengertian genah atau tempat;
Ma adalah matahari atau cahaya atau terang. Jadi menurut uraian ini kata
agama mengandung pengertian bahwa tempat yang kosong perlu diberi
penenerangan/sinar. Maksudnya ialah hati dan pikiran manusia yang masih
kosong perlu diisi sinar suci dari Tuhan agar menjadi terang. Sinar suci ini
berupa tuntunan ajaran Tuhan untuk mengatur perilaku manusia agar
menjadi bersusila dan berbudi. Karena itu dalam uraian selanjutnya dari
Sundarigama, kata agama itu disamakan dengan Ambek, yaitu perilaku
yang perlu diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ajaran Tuhan.
Ugama. Kata Ugama ini terdiri atas u, ga, dan ma, yang mengandung
pengertian sebagai berikut: U adalah udaka, tirta atau air suci; Ga berarti
geni atau api; Ma kependekan dari maruta yang berarti angin atau udara.
Dari uraian suku kata tersebut yang dimaksudkan dengan kata ugama
adalah suatu ajaran tentang penggunaan sarana air, api, dan udara dalam
memuja Tuhan. Maksudnya ialah agar umat manusia di dalam melakukan
pemujaan terhadap Tuhan selalu menggunakan sarana berupa air suci
(tirta), api (berupa dupa, dipa dan lain sebainya), dan udara (berupa mantra,
kidung, gamelan atau bunyi-bunyian, wangi-wangian, dan lain-lainl).
7
Dengan menggunakan sarana-sarana ini manusia akan lebih cepat
mendekatkan atau menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Karena itu
perilaku dalam hal ugama disamakan dengan ulah, yaitu tingkahlaku
manusia dalam melaksanaan pemujaan terhadap Tuhan melengkapi diri
dengan berbagai sarana sehingga tercapai kesejahteraan baik di sekala
maupun di niskala.
Igama. Kata igama ini terdiri atas suku kata i, ga, dan ma, yang mempunyai
makna: I adalah Iswara atau Siwa; Ga berarti angga atau badan sarira; Ma
bermakna amerta atau hidup. Berdasarkan atas pengertian ini maka igama
dimaksudkan sebagai suatu sikap manusia atas pengakuaannya bahwa
badan sariranya dapat hidup atas karunia dari Iswara atau Siwa (Tuhan).
Karena itu igama ini disamakan dengan Idep, yaitu sikap jiwa manusia yang
menyadari kejati diriannya. Dengan mempelajari igama (tattwa agama)
maka manusia bertambah sadar tentang sangkan paraning dumadinya,
asal-usul dan tujuan hidupnya di dunia ini. (Ngurah Nala, 1993: 5)
Jika diteliti lebih mendalam lagi, maka yang dikupas di dalam lontar
Sundarigama, sebenarnya merupakan suatu rangkaian kesadaran manusia
tentang dirinya serta cara pendekatannya dengan Sang Maha Pencipta agar
dapat hidup sejahtera lahir batin di mercapada ini. Di dalam ajaran tri-agama
ini (agama-ugama-igama), manusia itu diibaratkan sebagai suatu tempat yang
kosong yang memerlukan isi berupa sinar terang yang abadi. Untuk
mendapatkan sinar ini maka manusia harus melakukan pemujaan dengan
mempergunakan sarana berupa air, api, dan udara. Dengan dilaksanakannya
pemujaan ini, manusia mendapat sinar suci tersebut, dan timbullah kesadaran
8
di dalam diri manusia akan kejatidiriannya. Dia sadar bahwa manusia itu ada
dan hidup adalah berkat adanya Iswara (Tuhan).
Tujuan dari Agama Hindu adalah mencapai kedamaian rohani dan
kesejahteraan hidup jasmani. Dalam pustaka suci Veda disebutkan
“mokshartham jagadhitaya ca iti dharma” yang artinya dharma atau agama
adalah untuk mencapai moksa (mokshartham) dan mencapai kesejahteraan
hidup mahkluk (jagadhita). Moksa juga disebut “mukti” artinya mencapai
kebebasan jiwatman atau kebahagiaan rohani yang langgeng (Sudharta dan
Atmaja, 2001:5).
Agama Hindu merupakan pengetahuan, dharma dan kebenaran yang
kekal abadi sebagai pedoman yang sangat universal. Karakter Agama Hindu
yang sering dinyatakan sebagai agama yang luwes dan fleksibel bukanlah
sesuatu yang aneh karena sesungguhnya padanya muncul cabang dan ranting
kepercayaan-kepercayaan lainnya) tumbuh dan berkembang. Dengan kata
lain, pengetahuan akan segala macam konsep ketuhanan (isme) ada dalam
Hinduisme. Di dalam Hinduisme terdapat keyakinan: (1) animisme (keyakinan
akan segala sesuatu, di alam semesta didiami roh atau jiwa), (2) dinamisme
(keyakinan terhadap kekuatan-kekuatan alam), (3) anhropomorfisme
(keyakinan yang menggambarkan sifat-sifat Tuhan seperti sifat-sifat manusia),
(4) polytheisme (keyakinan akan adnya banyak dewa, dalam Hinduisme, adnya
banyak dewa merupakan manifestasi dari satu Tuhan sebagai realitas yang
tunggal sebagai perlambang aspek-aspek yang berbeda-beda), (5) monism
(keyakinan terhadap keesaan Tuhan merupakan hakikat alam semesta. Esa
adalah segalanya dan segalanya berada dalam yang esa), (6) pantheisme
9
(keyakinan di mana-mana serba Tuhan atau segala sesuatu adalah Tuhan),
(7) totemisme (keyakinan pada benda, tumbuh-tumbuhan, atau hewan-hewan
yang dianggap suci karena dianggap penjelmaan dewa),
(8) henotheisme/kathenoisme (keyakinan terhadap adanya dewa tertinggi yang
pada suatu masa akan digantikan oleh dewa lain sebagai dewa tertinggi),
(9) monotheisme (keyakinan yang mempercayai dan menyembah satu Tuhan);
dalam pengertian yang benar, bukan dalam pandangan komparasi yang
digunakan hanya untuk mencari kebenaran sepihak yang subjektif (Donder,
2006:138)
Hinduisme adalah kebenaran objektif yang intersubjektif, artinya
Hinduisme adalah kebenaran fakta yang menerima kebenaran dari manapun
sepanjang tidak bertentangan dengan kesemestaan. Hinduisme mampu
membimbing setiap manusia setapak demi setapak dari kebenaran yang amat
sederhana hingga kebenaran absolut yang tidak dapat ditafsirkan dengan akal
(Donder, 2006: 138).
Cakupan ajaran-ajaran pengetahuan dalam Agama Hindu sangat luas,
menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Agama Hindu bukanlah
agama yang mengedepankan sisi spiritualitas (membangun hubungan dengan
Tuhan) semata, namun juga tidak kalah pentingnya adalah membangun
harmonisasi antara sesame manusia dan juga sinergi antara manusia dengan
alamnya. Agama Hindu merupakan kepercayaan atau keyakinan melalui
ajaran-ajarannya yang bersumber dari wahyu (sabda suci) Ida Sang Hyang
Widhi Wasa tentang cara mengadakan hubungan, baik antara manusia dengan
Tuhan, manusia dengan sesama manusia, maupun manusia dengan alam
10
lingkungannya. Melalui pengamalan ajaran Agama Hindu dengan baik dan
benar dalam setiap aspek kehidupan manusia, harmonisasi hubungan antara
manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia, beserta
alam lingkungannya akan tercipta dan berjalan dengan baik.
2.2 Veda Sebagai Kitab Suci Agama Hindu
Kata Veda secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari
urat kata “vid” yang artinya mengetahui dan Veda berarti pengetahuan. Dalam
pengertian semantik Veda berarti “pengetahuan suci”, “kebenaran sejati’,
“pengetahuan tentang ritual”, “kebijaksanaan yang tertinggi”, pengetahuan
spiritual sejati tentang kebenaran abadi”, “ajaran suci atau kitab suci sumber
ajaran Hindu” (Titib, 1996: 13). Apabila diliat dari pengkodifikasiannya, Veda
tidak hanya sekedar kitab suci, namun lebih dari itu, merupakan pustaka suci
yang memuat berbagai macam pengetahuan, baik tentang tattwa (ajaran
ketuhanan/spiritualitas), susila (etika moralitas), acara (berbagai ritual dan
aktivitas keagamaan lainnya), referensi sejarah, mitologi, dan termasuk
pengetahuan dalam bidang sains.
Bahasa yang dipergunakan dalam Veda adalah bahasa Sanskerta.
Istilah atau nama Sanskerta sebagai nama bahasa ini dipopulerkan oleh
Maharsi Panini. Maharsi Panini pada waktu itu mencoba menulis sebuah kitab
Vyakarana, yaitu kitab tata bahasa Sanskerta yang terdiri dari 8 Adhyaya atau
bab yang terkenal dengan nama Astadhyayi yang mencoba mengemukakan
bahwa bahasa yang digunakan dalam Veda adalah bahasa dewa-dewa yang
dikenal pula dengan nama “daivivak” yang artinya bahasa atau sabda dewa
(Titib, 1996:16).
11
Untuk memahami kitab suci Veda, maka dalam mempelajarinya
baruslah dilakukan secara berjenjang atau bertahap. Maharsi Vyasa dalam
Vayy Purana I.20 menyatakan
Itihasa Puranabhyam vedam samuparmhayet, Bibhetyalpasrutad vedo mamayam praharisyadi.
Terjemahan:
Hendaknya Veda dijelaskan melalui sejarah (Itihasa) dan Purana (sejarah dan metologi kuna), Veda merasa takut kalau seseorang yang bodoh membacanya. Veda berpikir bahwa dia (orang yang bodoh) akan memukulmu (Titib, 1996:4).
Sloka di atas memiliki maksud bahwa dalam mempelajari Veda
hendaknya dimulai dari memahami Itihasa dan Purana terlebih dahulu.
Tujuannya adalah agar orang yang mempelajari Veda memiliki referensi yang
luas dari pemahaman tingkat paling sederhana sampai yang lebih dalam dan
luas. Dengan demikian diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang
ajaran-ajaran Veda secara menyeluruh dan lebih mendalam. Apabila Veda
tidak dipelajari secara berjenjang, tanpa dilandasi dasar pemahaman akan
Itihasa dan Purana terlebih dahulu, maka dikhawatirkan akan menimbulkan
kekeliruan dalam penafsiran, serta penyimpangan-penyimpangan dalam
pengimplementasian ajaran-ajarannya, sehingga hal tersebutlah yang menjadi
maksud pernyataan bahwa orang bodoh akan memukul Veda itu sendiri.
Veda merupakan tuntunan suci bagi seluruh umat Hindu. Oleh sebab
itu, penting bagi siapapun untuk mempelajarinya. Veda tidaklah diskriminatif,
sangat terbuka bagi semua kalangan profesi, bahkan bagi orang-orang non-
Hindu sekalipun. Yajurveda XXVI.2 menyatakan bahwa:
12
Yathemam vacam kalyanim avadani janebhyah, brahma rajanyabhyam sudraya caryaya ca svaya caranaya ca.
Terjemahannya:
Hendaknya disampaikan sabda suci ini kepada seluruh umat manusia, cendikiawan-rohaniawan, raja/pemerintahan/masya-rakat, para pedagang, petani dan nelayan, serta para buruh, kepada orang-orngku dan bahkan orang asing sekalipun (Titib, 1996:3)
Adapun pembagian atau kodifikasi Veda dapat diuraikan sebagai
berikut.
2.2.1 Kelompok Veda Sruti
Sruti adalah kitab yang disusun berdasarkan wahyu atau sabda suci
yang diturunkan langsung oleh Ida Sang HYang Widhi Wasa. Kitab Sruti
dinyatakan sebagai Veda yang sebenarnya (original) karena diterima melalui
pendengaran, yang diturunkan sesuai periodesasinya dalam empat kelompok
atau himpunan. Oleh sebab itu Veda Sruti disebut juga dengan Catur Veda
atau Catur Veda Samhita. Pembagiannya adalah:
a) Rgveda. Rgveda merupakan kitab yang dihimpun oleh Maharsi Pulaha.
Memuat nyanyian-nyanyian pujaan yang mengandung tendensi filosofis.
Inti ajaran Rgveda menekankan berbagai cara yang sangat kaya untuk
meningkatkan rasa bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b) Yajurveda. Dihimpun oleh Maharsi Waisampayana yang inti ajarannya
menekankan pada upacara ritual atau prosedur pelaksanaan yajna
(yadnya).
13
c) Samaveda. Dihimpun oleh Maharsi Jaimini. Disebut juga Nyanyian Veda
Suci, karena kitab ini pada intinya memuat tentang mantram-mantram
yang umumnya dilagukan pada upacara-upacara penting.
d) Atharvaveda. Disusun oleh Maharsi Sumantu yang inti ajrannya memuat
mantram-mantram untuk memperoleh pengampunan dosa dan karunia
dewa-dewa, mengusir kejahatan dan kehidupan yang sulit, dan juga
menghancurkan musuh.
Berdasarkan tradisi kuno yang ada dapatlah dijelaskan lebih detail
tetang pembagian kitab-kitab Veda dengan kitab-kitab pendukung yang terkait
dengan kitab wahyu yang kita kenal dengan Sruti itu. Umat Hindu yakin, selain
Catur Veda (Rgveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda), kitab-kitab
Brahmana, Aranyaka, dan Upanisad adalah juga kitab-kitab Sruti dan untuk
menyebutkan syair dari kitab-kitab Sruti adalah matra, sedang di luar kitab-kitab
Sruti, syair itu pada umumnya disebut sloka.
Lebih jauh tentang pembagian kitab-kitab Veda, berikut diuraikan kitab-
kitab itu yang dapat kita warisi:
Rgveda
Sakha : Sakala Samhita
Brahmana : Kausitaki, Aitareya
Aranyaka : Kausitaki, Aitareya
Upanisad : Kausitaki, Upanisad
Kalpa : (a) Srautasutra : Samkhayana, Asvalayana
(b) Grhyasutra : Samkhayana, Asvalayana, Sambavya
(c) Dharmasutra : Vasistha
14
Pratisakhya : Rkpratisakhya
Anukramani : Arsanukramani, Chandonukramani, Devtanukramani,
Anuvakanukramani, Suktanukramani, Rgvidhan, Brhaddevata,
Rksarvanukramani, Madhaviyanukramani.
Yajurveda
Sukla Yajurveda
Sakha : Vajasaneyi (Madhyadina), Kanva
Brahmana : Sathapata
Aranyaka : Brnadaranyaka, Jaiminiyopanisad (Talavakara)
Upanisad : Brhadaranyaka, Isavasya (Isa Upanisad)
Kalpa : (a)Srautasutra : Katyayana
(b) Grhyasutra : Parasara
Pratisakhya : Suklayajuh Pratisakhya
Anukramani : Suklayajuhaanukramani, Nigamaparisista, Yajurvidhna
Krsna Yajurveda
Sakha : Taitiriya, Maitrayani, Katha
Brahmana : Taittiriya
Aranyaka : Taittiriya, Maitrayani
Upanisad : Taittiriya, Maitrayani, Katha, Svetasvatara.
Kalpa : (a) Srautasutra : Baudhayana, Apastamba, Baikhanasa,
Bhadravaja, Manava, Hiranyakesi
(b) Grhyasutra : Apastamba, Baikhanasa, Bharadvaja,
Manava, Hiranyakesi
(c) Dhrmasutra : Baudayana, Apasthamba
15
Pratisakhya : Taitiriya Pratisakhya
Anukramani : Yajus Sarvanukramani, Kandanukramani
Samaveda
Sakha : Kauthumi, Jaiminiya, Ranayaniya
Brahmana : Tandya (Pancavimsa, Sadvimsa, Mantra, Chandogya),
Arseya, Vamsa amhitopanisad, Jaiminiyopanisad
Talavakara, Samavidhana
Aranyaka : Jaimniyopanisad atau Talavakara
Upanisad : Chandogya, Kena
Kalpa : (a) Srautasutra : Masaka, Katyayana, Drhyana
(b) Grhyasutra : Gobhila, Khadira
(c) Dhramasutra : Gautama
Pratisakhya : Samapratisakhya
Anukramani : Samavidhana
Atharvaveda
Sakha : Saunaka
Brahmana : Gopatha
Upanisad : Prasna, Manduka, Mandukya
Kalpa : (a) Srautasutra : Vaitana
(b) Grhyasutra : Kausika
Pratisakhya : Atharva Pratisakya
Anukramani : Brhatsarvanukramani, Atharvavidhana
16
Demikian antara lain pembagian kitab-kitab Veda, khususnya kitab-kitab
Sruti dengan kalpa (Vedanga), Pratisakhya dan Anukrmaninya yang dapat kita
jumpai, kini marilah kita bahas spintas isi yang terkandung dalam kitab Veda.
Bila kita mempeajari secara keseluruhan mantra-mantra Veda (Catur
Veda), termasuk pula kitab-kitab Brahmana, Aranyaka, dan Upanisad, maka
pada garis besarnya ajaran Veda dapat dikelopokkan ke dalam empat
kelompok isi, yang masing-masing dapat dikembangkan lagi sebagai
pengetahuan yang berdiri sendiri, sebagai berikut
a) Kelompok yang membahas aspek Vijnana, yaitu kelompok mantra yang
membahasa bermacam aspek pengetahuan, baik pengetahuan alam
sebagai ciptaann-Nya, termasuk pula teologi, kosmologi dan lain-lain
yang bersifat methaphisik. Kata Vijnana berarti kebijaksanaan tertinggi
(realization of knowledge). Intinya mungkin sangat singkat atau pendek,
kadangkala sangat sulit untuk memahami apa yang terkandung di balik
mantra atau ungkapan melalui mantra-mantra itu. Demikian pula
penggunaannnya terlebih lagi digunakan dalam rangkaian doa atau
stave, sehingga hal itu kadang-kadang kita anggap hal yang biasa dan
bukan merupakan pengetahuan yag disebut Vijnana. Ini akan
bertambha jelas setelah kita membaca Yajurveda, bahwa Veda
berisikan berbagai pengetahuan yang diperlukan oleh manusia guna
meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang paling menonjol
dalam aspek Vijnana ini adalah aspek aspek yang memberi keterangan
dasar pandangan filsafat dan methapisika berdasarkan Veda.
17
b) Kelompok yang membahas aspek Karma, yaitu kelompok mantra
mengenai berbagai aspek atau jenis Karma atau Yajna sebagai dasar
atau cara dalam mencapai tujuan hidup manusia. Pembahasan secara
mendalam mengenai hal ini kemudian dikembangkan di dalam kitab-
kitab Kaalpasutra sebagai pengembangan lebih jauh kitab-kitab
Brahmana.
c) Kelompok yang membahas aspek Upasana, yaitu kelompok mantra
yang membahas segala aspek yang ada kaitannya dengan petunjuk dan
cara untuk mendekatkan diri dengan sthana Sang HYang Widhi.
Kelompok mantra ini menjadi dasar berkembangnya system atau ajaran
Yoga.
d) Kelompok yang membahas aspek Jnana, yaitu kelompok mantra yang
membahas segala aspek pengetahuan secara umum sebagai ilmu
murni. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa kita tidak
mendapatkan gambaran secara lengkap bagaimana ilmu itu, kecuali
hokum-hukum tertentu yang kemudian kalua kita kembangkan akan
menjadi ilmu yang berdiri sendiri, sebagai contoh Vaidikaganitam
(matematika Veda), Ayurveda dan sebagainya. Ayurveda ini sudah
sejak lama dikembangkan dalam perguruan modern (Ayurvedic college)
sebagai bidang yang berdiri sendiri, berdampingan dengan system
pengobatan modern. Ini berarti di dalam Veda terdapat pengetahuan
atau ilmu murni yang bisa dikembangkan lagi.
Sebagai telah disebutkan, sebenarnya pengelompokan ke dalam empat
kelompok atau topik di atas, dapat pula disederhanakan menjadi dua aspek,
18
yaitu ajaran yang mengandung aspek Karmakanda, yakni yang menyangkut
ajaran karma, Yajna dan Upasana, dapat dijumpai dalam kitab-kitab Samhita,
Brahmana, dan Aranyaka, sedang aspek lainnya adalah Jnanakanda, yang
dapat kita jumpai dalam Samhita, Aranyaka, dan Upanisad.
Selanjutnya tentang isi Veda dapat pula kita menganalisa dengan
menggunakan dasar-dasar pendekatan sesuai kitab Bhagavadgita, yakni
mengelompokkan isi Veda dalam 5 topik, sebagai berikut:
a) Yang mengandung ajaran Bhakti atau Bhaktiyoga.
b) Yang mengandung ajaran Karma atau Karmayoga.
c) Yang mengandung ajaran Jnana atau Jnanayoga.
d) Yang mengandung ajaran Rajayoga, dan
e) Yang mengandung ajaran Vibhutiyoga atau ajaran yang bersifat mistis.
Mengingat mantra-mantra Veda sukar dipahami dan mungkin kurang
menarik minat bagi umat yang awam di bidang kerohanian para rsi menyusun
kitab-kitab sastra sebagai alat bantu memahami ajaran tersebut. Tentang hal
ini, Maharsi yang juga Adikavi Valmiki menyakan dalam karya agung beliu
Ramayana, bahwa disusunnya mahaviracarita ini sebagai sarana untuk lebih
memudahkan umat memahami kitab suci Veda. Demikian pula Maharsi
Vyasa atau Krsnadvipayana yang juga berbhiseka Vedavyasa menegaskan
untuk memahami Veda perlu dijelaskan melalui Itihasa dan Purana.
19
2.2.2 Kelompok Veda Smrti
Smerti adalah Veda yang disusun kembali berdasarkan ingatan para
Maharsi yang disertai dengan penafsiran-penafsiran. Smerti merupakan
kelompok kitab kedua setelah Sruti dan dianggap sebagai kitab hukum Hindu
karena di dalamnya banyak dimuat tentang aturan Hindu yang disebut Dharma.
Oleh karena itu, kitab Smrti ini dinyatakan dalam berbagai kitab sebagai kitab
Dharmasastra (Titib, 1996:128). Pembagiannya secara garis besar
dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yakni Vedangga dan Upaveda,
yang diuraikan sebagai berikut.
a. Kelompok Vedangga, yang terdiri dari enam bidang, yakni:
1) Siksa (ilmu phonetika), yang isinya memuat petunjuk-petunjuk tentang
cara-cara pengucapan mantram serta tinggi rendah tekanan suara.
2) Vyakarana (ilmu tata bahasa), yang berisi tentang tata bahasa yang
benar digunakan dalam Smrti dan juga sastra klasik Sanskerta.
3) Nirukta (ilmu etimologi), yang memuat berbagai penafsiran otentik
mengenai kata-kata yang terdapat dalam Veda.
4) Chanda (ilmu irama/lagu), yang khusus membahas aspek ikatan bahasa
yang disebut lagu. Sejak dari sejarah penulisan Veda, Chanda sangat
berperan, karena semua ayat-ayat tersebut dapat dipelihara secara
turun-temurun dengan nyanyian yang mudah diingat.
5) Jyotisa (ilmu astronomi dan astrologi), yang memuat perhitungan hari-
hari yang tepat dalam melaksanakan upacara-upacara yajna. Jyotisa
menggambarkan bagaimana tata surya, bulan, dan benda-benda
20
angkasa lainnya yang dianggap mempunyai pengaruh dalam
pelaksanaan yajna.
6) Kalpa, yang merupakan kelompok Vedangga terbesar. Menurut isinya,
Kalpa terbagi atas beberapa bidang yakni Srauta (memuat berbagai
ajaran tata cara melakukan yajna dan lainnya yang berhungan dengan
upacara keagamaan), Grhya (memuat ajaran peraturan yajna yang
harus dilaksanakan oleh orang-orang yang berumah tangga),
Dharmasutra (memuat aspek peraturan hidup bermasyarakat dan
bernegara), dan Sulvasutra (memuat tentang peraturan dan tata cara
membuat tempat peribatan (Netra, 1994:15)
b. Kelompok Upaveda, yang terdiri dari:
1) Itihasa, yang merupakan jenis epos, yang terdiri dari Ramayana dan
Mahabharata. Kitab Ramayana ditulis oleh Rsi Walmiki yang isinya
dikelompokkan dalam tujuh kanda, yakni:
- Ayodhya Kanda
- Bala Kanda
- Kiskinda Kanda
- Sundara Kanda
- Yudha Kanda
- Utara Kanda
Sedngkan Kitab Mahabharata disusun oleh Maharsi Wyasa yang terdiri
dari delapanbelas parwa yang terdiri dari:
- Adiparwa
- Sabhaparwa
21
- Wanaparwa
- Wirataparwa
- Udyogaparwa
- Bhismaparwa
- Dronaparwa
- Karnaparwa
- Salyaparwa
- Sauptikaparwa
- Striparwa
- Santiparwa
- Anusasanaparwa
- Aswmedhikaparwa
- Asramawasikaparwa
- Mausalaparwa
- Mahaprastanikaparwa
- Swargarohanaparwa
Di antara kedelapanbelas parwa tersebut, dalam Bhismaparwa terdapat
kitab Bhagawadgita yang terkenal dengan wejangan-wejangan Sri Krsna
kepada Arjuna. Isinya merupakan filsafat yang sangat tinggi serta dikenal pula
dengan sebutan Panca Veda.
2) Purana, yang merupakan kumpulan cerita-cerita kuno yang menyangkut
penciptaan dunia, cerita tentang dewa-dewa, raja-raja, dan para rsi.
Kitab Purana dibagi mnjadi delapan belas yakni:
- Brahmanda Purana
22
- Brahmavaivarta Purana
- Markandya Purana
- Bhawisya Purana
- Wamana Purana
- Brahma Purana
- Wisnu Purana
- Narada Purana
- Bhagavata Purana
- Garuda Purana
- Padma Purana
- Waraha Purana
- Matsya Purana
- Kurma Purana
- Lingga Purana
- Siwa Purana
- Skanda Purana
- Agni Purana
3) Arthasastra, yang memuat tentang ilmu pemerintahan Negara. Isinya
merupakan pokok-pokok pemikiran ilmu politik. Sebagai cabang ilmu,
jenis ilmu ini juga disebut dengan Nitisastra, Rajadharma, atau
Dandaniti.
4) Ayurveda, yakni kitab yang memuat tentang ilmu kesehatan,
pengobatan serta filsafat kehidupan, baik etis maupun medis.
23
5) Gandharvaveda, yakni kitab yang membahas tentang berbagai aspek
cabang ilmu seni.
Kitab suci Veda disebutkan memiliki sifat “Anadi-Ananta” karena ajaran-
ajarannya sangatlah relevan, tidak pernah lekang dengan perkembangan
zaman. Pemahaman tentang ajaran-ajarannya mutlak diperlukan agar umat
Hindu memiliki dasar yang kuat dalam setiap pelaksanaan aktivitas
keagamaannya.
2.3 Kerangka Dasar Agama Hindu dan Relevansinya Dengan Budaya
Lokal
Ajaran Agama Hindu bersumber pada kitab suci Veda yang merupakan
wahyu (sabda suci) Tuhan Yang Maha Esa. Agama Hindu memiliki tiga
kerangka pokok yang menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan ajaran-
ajarannya. Ketiga kerangka dasar tersebut adalah Tattwa, Susila, dan Acara.
Tattwa merupakan intisari, filsafat, kebenaran yang menjadi dasar ajaran
agama. Tattwa dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan thatness, ke-itu-
an, yaitu realitas absolute, realitas terakhir. Ajaran Tattwa adalah ajaran
tentang realitas terakhir itu (Sura dalam Sedhawa, 2006:110). Tattwa
merupakan ajaran yang mencakup tentang fisafat Ketuhanan yang dalam
prakteknya diaktualisasikan dalam upacara-upacara yadnya, maupun
pengamalan tingkah laku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
Susila merupakan etika, tingkah laku yang mulia dalam beragama,
Susila adalah kata Saskerta yang terdiri dari kata “su” yang artinya baik, mulai
dan “sila” yang artinya perilaku/dasar. Jadi susila artinya perilaku yang mulia
24
dengan ajaran Veda (Adiputra, 2003:64). Susila berkaitan dengan tingkah laku
manusia. Susila atau etika moral merupakan aturan yang diyakini manusia
sebagai penuntun dalam hidup, baik secara individu maupun kehidupan
bermasyarakat beserta lingkungannya.
Acara merupakan praktek-praktek ajaran agama yang berupa aktivitas
ritual atau upacara. Kata Acara dalam kaitannya dengan acara Agama Hindu
berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya perbuatan atau tingkah laku yang
baik, adat-istiadat, tradisi atau kebiasaan yang merupakan tingkah laku
manusia baik perorangan maupun kelompok manusia yang didasarkan atau
kaidah-kaidah hukum yang ajeg. Sesuai dengan konsep Tri Krangka Agama
Hindu, Acara merupakan lapisan paling luar yang terdiri dari aktivitas
keagamaan dalam hubungannya untuk mendekatkan diri dengan Ida Sang
Hyang Widhi Wasa.
Ketiga bagian dari kerangka agama itu tidak dapat dipisah-pisahkan
pengamalannya. Tattwa, Susila, dan Acara patut diamalkan bersamaan dalam
setiap tindakan. Hilangnya salah satu dari ketiga unsur tersebut bisa
menjadikan pengamalan ajaran Agama Hindu menjadi tidak sempurna.
Pengamalan Tattwa tanpa Susila dan Acara menjadi gersang dan kering.
Demikian pula pengamalan Susila tanpa Tattwa dan Acara menjadi tampak
tidak semarak dan menjurus pada perilaku yang kaku atau ekstrim. Acara tanpa
Tattwa dan Susila bisa menjadikan tindakan pemborosan dan memunculkan
tradisi yang tanpa dasar kebenaran (Adiputra, 2003:22). Pelaksanaan ajaran
Agama Hindu di berbagai daerah tampak berbeda, terutama dalam aspek
Acara atau ritual. Agma Hindu dengan karakteristik luwes, fleksibel, dan adaptif
25
terhadap kepercayaan lokal mampun memberikan nilai keagamaan secara
harmonis. Sebaliknya kepercayaan lokal menanggapi secara positif
kedatangan agama Hindu dengan karakteristiknya sebagai suatu yang
komplementer atas keyakinan yang sudah ada. Terjadinya proses akulturasi
budaya antara agama Hindu tradisi lokal inilah yang menyebabkan
pelaksanaan ajaran Agama Hindu menjadi tampak berbeda meskipun
landasan filosofisnya adalah sama.
Agama dan budaya sesungguhnya secara hakikat merupakan dua hal
yang berbeda. Namun dalam praktek-praktek keagamaan menjadi dua hal
yang tidak terpishkan satu dengan yang lain. Agama merupakan kepercayaan
kepada Tuhan beserta segala sesuatu yang bersifat sangat abstrak yang
didasarkan pada nilai rasa dalam diri setiap individu. Sedangkan budaya
adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan,
kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan yang lain,
serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat
(Taylor dalam Setiadi dkk, 2008:27). Budaya merupakan hasil dari
perkembangan dan pengembangan akal dan pikiran manusia, di mana konsep
kebudayaan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, kata buddhayah, yaitu
bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Oleh karena itu,
kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi
dan akal (Adhiputra, 2010:44).
Salah satu contoh nyata adalah Agama Hindu di Bali yang praktek
ritualnya sangat berbeda dengan Agama Hindu di India. Hal ini disebabkan
karena adanya sinkritisme ajaran Hindu dengan budaya lokal Bali. Di samping
26
itu pula banyak daerah di Bali yang memiliki tradisi-tradisi keagamaan yang
bersifat lokal tersendiri yang terkadang tidak dapat dijumpai di daerah lainnya.
Adanya perbedaan tradisi keagamaan yang bersifat kearipan lokal atau local
genius inilah yang menjadikan beberapa daerah di Bali memiliki keunikan dan
cirri khas tersendiri. Kearipan lokal dalam beragama bila dilihat dari sistem
kehidupan umat Hindu di Bali yang sangat pluralistik merupakan sebuah media
yang dapat memfasilitasi umatnya dalam melaksanakan sistem
kepercayaannya. Adanya perbedaan-perbedaan kearifan lokal tersebut
bukanlah suatu bentuk penyimpangan karena secara esensi, hal ini masih
sangat sesuai dengan ajaran Hindu itu sendiri. Sesuai dengan ajaran yang
tertuang dalam Kitab Bhagavadgita IV.11 yang menjelaskan bahwa:
Ye yatha mam prapadyante tams tathai’va bhajamy aham, mama wartmanuwartante manusyah partha savasah
Terjemahannya
Dengan jalan bagaimanapun orang-orang mendekati dengan jalan yang sama itu juga Aku memenuhi keinginan mereka. Melalui banyak jalan manusia mengikuti jalan-Ku O Partha (Mantra, 2007:65)
Lebih jauh, dalam kitab Manawadharmasastra II..6, dijelaskan bahwa:
Idanim dharma pramanamyaha: vedo khilo dharma mulam smrtisile ca tadvidam. acarascaiva sadhunam atmanastustir eva ca
Terjemahannya:
Seluruh pustaka suci Veda merupakan sumber pertama dari dharma, kemudian adat-istiadat, lalu tingkah laku yang terpuji dari orang-orang bijak yang mendalami ajaran suci Veda; juga tata
27
cara kehidupan orang suci dan akhirnya kepuasan pribadi (Pudja dan Sudharta, 2004:31)
Petikan Manawadharmasastra tersebut memberikan penjelasan secara
lebih terperinci bahwa dalam menjalankan ajaran Agama Hindu yang memiliki
banyak variasi dari aspek Acara, maka hendaknya berpedoman pada Veda
sebagai sumber yang paling utama, lalu adat-istiadat yang berlaku, sampai
pada akhirnya adalah kepuasan pribadi (atmanastusti/atmatusti) yang menjadi
pedoman dan tujuan akhir dari setiap pelaksanaan praktek ritual.
Terkait dengan hal tersebut, maka dalam hal ini, peran agama sebagai
roh kebudayaan secara garis besar ada tiga yakni:
1) Memberi makna bagi kebudayaan tersebut, baik makna filosofis, etika,
dan aktivitas pelaksanaannya;
2) Memberi nilai religius bagi suatu kebudayaan, tradisi, maupun
masyarakat yang melaksanakannya;
3) Memberikan koreksi bagi unsur-unsur kebudayaan yang kurang sesuai
dengan nilai-nilai agama sehingga menjadi selaras dengan nilai-nilai
agama.
Jadi pada intinya, agama memberi nilai dan makna pada budaya, dan
budaya memberi format bentuk dan menunjukkan eksistensi agama.
Berdasarkan hal inilah maka pelaksanaan ajaran agama di berbagai daerah
memiliki keberagaman dan perbedaan sesuai dengan sistem kebudayaan
setempat yang dianut yang disebut kearifan lokal. Nilai-nilai filosofis dan magis
ajaran Agama Hindu yang dibingkai oleh kearifan lokal akan membangun dan
memperkokoh identitas (jati diri) umat Hindu di berbagai daerah dan menjadi
identitas budaya dari masyarakat pendukungnya.
28
III SIMPULAN
Cakupan ajaran-ajaran pengetahuan dalam Agama Hindu sangat luas,
menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Agama Hindu bukanlah
agama yang mengedepankan sisi spiritualitas (membangun hubungan dengan
Tuhan) semata, namun juga tidak kalah pentingnya adalah membangun
harmonisasi antara sesama manusia dan juga sinergi antara manusia dengan
alamnya. Agama Hindu merupakan kepercayaan atau keyakinan melalui
ajaran-ajarannya yang bersumber dari wahyu (sabda suci) Ida Sang Hyang
Widhi Wasa tentang cara mengadakan hubungan, baik antara manusia dengan
Tuhan, manusia dengan sesama manusia, maupun manusia dengan alamnya.
Melalui pengamalan ajaran Agama Hindu dengan baik dan benar dalam setiap
aspek kehidupan manusia, harmonisasi hubungan antara manusia dengan
Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia, beserta alam lingkungannya
akan tercipta dan berjalan dengan baik.
Kitab suci Veda disebutkan memiliki sifat “Anadi-Ananta” karena ajaran-
ajarannya sangatlah relevan, tidak pernah lekang dengan perkembangan
zaman. Pemahaman tentang ajaran-ajarannya mutlak diperlukan agar umat
Hindu memiliki dasar yang kuat dalam setiap pelaksanaan aktivitas
keagamaannya.
Jadi pada intinya, agama memberi nilai dan makna pada budaya, dan
budaya memberi format bentuk dan menunjukkan eksistensi agama.
Berdasarkan hal inilah maka pelaksanaan ajaran agama di berbagai daerah
memiliki keberagaman dan perbedaan sesuai dengan sistem kebudayaan
29
setempat yang dianut yang disebut kearifan lokal. Nilai-nilai filosofis dan magis
ajaran Agama Hindu yang dibingkai oleh kearifan lokal akan membangun dan
memperkokoh identitas (jati diri) umat Hindu di berbagai daerah dan menjadi
identitas budaya dari masyarakat pendukungnya.
30
IV KEPUSTAKAAN
Adiputra, I Gede Rudia, 2003. Pengetahuan Dasar Agama Hindu. Jakarta: Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara.
Atmaja, N.B., 2004. Kearipan Lokal Dan Agama Pasar, Denpasar: Bahan Matrikulasi S2 Kajian Budaya.
Donder, I Ketut, 2006. Brahmavidya: Teologi Kasih Semesta. Surabaya: Paramita.
Jalaludin,H, 2012. Psikologi Agama. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Gama I Wayan, 2002. Reformasi Agama Hindu Menuju Kebertahanan Sradha Dalam Menjawab Tantangan Masa Kini, Studi Kasus di Bali Tahun 1959-1998. Denpasar: tesis Unud.
Kaleran, Ida Pedanda Gde Ngurah. 2001. Sdhaka Dalam Konteks Kehidupan Masyarakat Hindu (Tinjauan Historis-Sosiologis) dalam Eksistensi Sadhaka Dalam Agama Hindu. Denpasar: Manik Geni.
Keene, Michael, 2010. Agama-Agama Dunia. Yogyakarta: Kanisius.
Koentjaraningrat, 1972. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: PT Dian Rakyat.
Mirsha, I Gusti Ngurah Rai dkk. 1994. Buana Kosa. Denpasar: Upada Sastra.
Pitana, I Gede (Editor). 1994. Dinamika Masyarakat Dan Kebudayaan Bali. Denpasar: BP.
Putra Agung, A.A.G. 1974. Perubahan Sosial Dan Pertentangan Kasta Di Bali Utara, 1924-1928. Yogyakarta: UGM.
Polloma Margaret M. 2003. Sosiologi Komtemporer (terjemahan) Jakarta :Raja Grafindo Persada.
Ritzer G. dan Goodman D.J. 2003. Teori Sosiologi Modern terjemahan Aliman dan. Jakarta: Predana Media.
Sanderson, S.K. 2003. Makro Sosiologi, terjemahan Farid Wajidi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sarapung, Elga. 2002. Kata Pengantar Dalam Pluralisme, Konflik dan Perdamaian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
31
Suata, I Putu Gede. 2001. Sumber Hindu Tentang Sadhaka, dalam Ekstensi Sadhaka Dalam Agama Hindu. Denpasar: Manik Geni.
Suweta, I Made. 1999. Fungsi Pendeta Hindu Untuk Pembobotan Keimanan Dalam Masyarakat Bali Yang Berubah. Denpasar: tesis Unud.
Sivananda Sri Svami. 1993. Intisari Ajaran Agama Hindu. Surabaya: Paramita.
Titib, I M. 2001 Eksistensi Sadhaka Kajian Sosiologi Religius Dan Filosofis, dalam Ekstensi Sadhaka Dalam Agama Hindu. Denpasar: Manik Geni.
Tim Pemda Propinsi Bali. 2003. Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu I-XV. Denpasar: Pemprop Bali.
Wianan I Ketut. 1993. Bagaimana Umat Hindu Menghayati Tuhan. Jakarta:Pustaka Manik Geni.
---------------, 2001. Sadhaka Dalam Kontek Yadnya Hindu. dalam Ekstensi Sadhaka Dalam Agama Hindu. Denpasar: Manik Geni.
---------------, 2002.Memelihara Tradisi Veda. Denpasar: BP
Wijadhaksa, Ida Pandita Mpu Siwa Karma. 2001. Sumber Sastra Tentang Eksistensi Sadhaka, dalam Ekstensi Sadhaka Dalam Agama Hindu. Denpasar: Manik Geni.
Yuda Triguna I.B. 1999. Perubahan Sosial Dan Respon Kultural Masyarakat Hindu di Bali. Denpasar Laporan Penelitian Unhi.
---------------, 2000a. Teori Tentang Simbol, Denpasar: Widya Dharma.
---------------, 2000b. Sentimen Kelompok Dan Gerakan Sosial Keagamaan. Denpasar: Makalah.
---------------, 2001. Redifinisi Simbolisme Masyarakat Hindu di Bali. Denpasar: Laporan Penelitian Unhi.




































![Kearifan Lokal [Huma-Talun; Masyarakat Adat Suku Sunda]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ae14a80cc3e9440059387/kearifan-lokal-huma-talun-masyarakat-adat-suku-sunda.jpg)