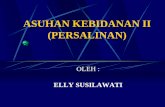ANALISIS POSKOLONIALISME DALAM NOVEL SALAH ASUHAN
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of ANALISIS POSKOLONIALISME DALAM NOVEL SALAH ASUHAN
ANALISIS POSKOLONIALISME DALAM NOVEL SALAH ASUHAN:BAB SATU SAMPAI DENGAN SEMBILAN
MakalahDiajukan untuk Memenuhi Salah Satu SyaratLulus Mata Kuliah Kajian Prosa Nusantara
Oleh:Christopher Allen Woodrich
NIM: 084114001
PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIAJURUSAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS SANATA DHARMAYOGYAKARTA
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa makalah yang
saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang
lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan
daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.
Yogyakarta,................
Penulis
Christopher Allen
Woodrich
2
KATA PENGANTAR
Atas bantuan mereka dalam penyelesaian makalah ini
saya ingin ucapkan terima kasih kepada orang-orang
berikut:
Trifosa Sie Yulyani Retno Nugroho, atas
dukungannya dalam semua tugas akademik.
S. E. Peni Adji, untuk segala ajarannya tentang
teori-teori kajian sastra.
Abdoel Moeis untuk karangannya yang begitu
menarik dan penuh makna.
Makalah ini tidak sempurna dan apabila terjadi
kekurangan saya mohon maaf lebih dahulu. Terima kasih.
3
Yogyakarta, ………………….. 2009
Christopher Allen
Woodrich
NIM: 084114001
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ...................................... i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .......................... ii
KATA PENGANTAR ..................................... iii
DAFTAR ISI ......................................... iv
4
BAB I: PENDAHULUAN ................................ 1
A. Latar Belakang Masalah .................. 1
B. Tujuan Analisis ....................... 1
C. Sistematika Penyajian ................. 1
BAB II: ANALISIS STRUKTURAL ........................ 3
A. Narasi .................................. 3
B. Alur Cerita ............................. 3
1)
Perkenalan .................................... 4
2)
Timbulnya Konflik ............................. 4
3) Peningkatan Konflik ................... 4
C. Latar ................................... 4
1) Latar Waktu ........................... 4
2) .......................................Latar
Tempat 5
3) .......................................Latar
Sosial Budaya ...................................... 6
D. Penokohan ............................... 6
1) Hanafi ................................ 6
2) Corrie Du Busée ....................... 7
3) Mariam ................................ 8
4) Tuan Du Busée ......................... 8
5
5)
Rapiah .......................................9
BAB III: ANALISIS POSKOLONIAL .................. 10
BAB IV: PENUTUP ............................... 14
DAFTAR PUSTAKA .................................... 15
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Walaupun selama zaman Balai Pustaka Indonesia
dijajah oleh Belanda, karya-karya sastra dari zaman itu
masih mempunyai pesan yang mengindonesia dan mencerminkan
kebudayaan lokal. Ada pula pesan-pesan nasionalis yang
disembunyikan dalam teks.
Demikian pula di Salah Asuhan. Sebagai karya Balai
Pustaka, sebelum diterbit Salah Asuhan sudah disensor oleh
penguasa Belanda. Namun, masih ada perasaan yang terbawa
dalam teks, diantara lain keinginan untuk keseimbangan,
takut pada budaya luar, dan keperluan untuk mempunyai
identitas sendiri.
Mengapakah seorang Pribumi menjadi bagai orang
Belanda? Bagaimanakah pengaruh keputusan itu dalam
kehidupan dan lingkungannya? Apakah hidup selayaknya
ketika ada lebih dari satu budaya? Dengan menjawab
pertanyaan ini, dalam karyanya Abdoel Moeis mencerminkan
ketakutan rakyat Indonesia.
6
B. Tujuan Analisis
Tujuan dari makalah ini adalah menganalisis bab satu
sampai dengan sembilan dari buku Salah Asuhan. Untuk itu,
akan digunakan metode poskolonial, yaitu teori yang
menganalisis keadaan di suatu negara mantan penjajahan.
C. Sistematika Penyajian
Makalah ini dibagi menjadi empat bab, tujuh subbab,
dan sebelas sub-subbab. Bab satu adalah bab pendahuluan,
yang berfungsi sebagai pengantar. Bab ini dibagai menjadi
tiga subbab dan menjelaskan latar belakang masalah,
tujuan dan metode analisis, dan sistem penyajian.
Bab dua adalah analisis struktur Salah Asuhan dari bab
satu sampai dengan sembilan; ini dibagai dalam empat
subbab dan sebelas sub-subbab. Bab ini berfungsi sebagai
informasi latar belakang yang menjelaskan bentuk cerita,
plot, narasi, dan sebagainya; informasi ini akan
diperlukan untuk memahami analisis poskolonial. Terdapat
dalam bab ini adalah penjelasan narasi, alur cerita,
latar, dan penokohan dalam cerita Salah Asuhan.
Bab tiga adalah analisis Salah Asuhan dari sudut
pandang poskolonialisme. Dalam bab ini akan dilihat
7
kebudayaan Indonesia, keraguan Indonesia, dan pula rasa
kedaulatan Indonesia yang tercermin dalam Salah Asuhan.
Bab empat adalah penutup. Penutup ini merupakan
kesimpulan dari makalah ini.
8
BAB II: ANALISIS STRUKTURAL
A. Narasi
Dalam Salah Asuhan narasi ada di bentuk orang
ketiga maha-tahu. Ini terbukti karena narator mengetahui
pikiran semua tokoh utama. Contohnya:
“Semalam-malaman itu Hanafi tidak tidur
sekejap juga. Rindu dan cinta, kepada Corrie
sekonyong—konyong sudah berbalik menjadi dendam
dan benci. Mengertilah ia, bahwa gadis itu
sudah mempermain-mainkannya, seolah-olah
dipergunakan buat perintang-rintang hati dan
buat penyingkat-nyingkatkan waktu dalam pakansi
(Moeis, 2009: 59).
Dan:
“Semalam-malaman itu Corrie tidak merasai
tidur nyenyak. Setiap saat ia bertanya dalam
hatinya, “Cintakah ia pada Hanafi?” Tapi
senantiasa didengarnya pula sahutan “Oh! Anak
Belanda dengan orang Melayu, bagaimana boleh
jadi! Tapi seketika itu juga berbunyi pula
suara “Orang Melayu boleh disamakan haknya
dengan orang Eropa (Moeis, 2009: 34).
9
Ini juga terbukti karena ada bab dengan tokoh utama
berbeda; kadang kala tokoh utama lain tidak muncul
sepanjang bab itu. Contohnya, dalam bab enam (Terbang
Membubung ke Langit Hijau), tokoh utama adalah Corrie
tanpa Hanafi muncul sama sekali. Sedangkan, dalam bab
delapan (Istri Pemberian Ibu), Hanafi dan ibunya
difokuskan tetapi Corrie tidak muncul.
B. Alur Cerita
Konflik utama tidak diselesaikan dalam bab-bab yang
dianalisis. Akibatnya, kedua bagian plot itu tidak akan
dibahas dalam seksi ini.
1) Perkenalan
Perkenalan dalam Salah Asuhan terjadi pada ketiga bab
pertama. Dalam bab pertama Hanafi dan Corrie
diperkenalkan, kemudian pada bab kedua Tuan Du Busée
diperkenalkan. Dalam bab ketiga Mariam diperkenalkan.
Pada bab ketiga tokoh utama terakhir dibicarakan, tetapi
dia baru diperkenalkan pada bab delapan.
2) Timbulnya Konflik
10
Konflik utama Salah Asuhan, yaitu ketidakcocokan
Hanafi dengan adat setempat, sudah ditandai dalam bab
satu. Konflik ini mulai benar-benar jelas pada bab tiga
ketika Hanafi berbicara dengan Mariam; rasa bencinya
terhadap bangsa Minangkabau kelihatan jelas. Walaupun
ibunya sedih akan perbuatan anaknya, dia hanya bisa
terima. Akibatnya, konflik tidak bisa cepat selesai.
3) Peningkatan konflik
Konflik meningkat selama berbab-bab, tetapi ada pula
yang cepat dipecahkan. Konflik utama dikembangkan dengan
kuat pada bab tiga, tujuh, delapan, dan sembilan.
Kebencian Hanafi atas semua kebudayaan Minangkabau
dicerminkan jelas dalam gaya pembicaraannya dengan Mariam
dalam bab tiga. Dalam bab delapan, digambarkan bagaimana
Hanafi suruh orang-orang yang menyiapkan pernikahannya
untuk menggunakan cara Barat.
C. Latar
1) Latar Waktu
Cerita ini tidak punya tanggal atau tahun yang
ditentukan, maka dapat dimengerti bahwa cerita terjadi
pada tahun pertama terbitnya Salah Asuhan, yaitu pada tahun
1928. Ini juga dicerminkan dengan beberapa hal seperti
11
media komunikasi (surat), pemerintah (penjajahan
Belanda), dan kendaraan (kereta angin dan mobil).
Ketujuh bab pertama terjadi dalam waktu dua hari.
Cerita mulai subuh hari dengan pertemuan di antara Hanafi
dan Corrie dan perjanjian untuk mereka bertemu kembali
hari berikutnya. Karena cerita lanjut beberapa hari
berturut-turut, ada bab yang terjadi di siang hari dan
ada pula bab yang terjadi di malam hari.
Setelah Hanafi rela menikah dengan Rapiah, cerita
dimulai kembali setelah waktu dua tahun. Oleh karena
waktu sebanyak itu sudah berlalu, ada banyak perubahan
dalam fisik dan keadaan tokoh. Contohnya, Hanafi sudah
beranak.
Cuaca dan suasana selain jam tidak digambarkan
secara detail. Oleh karena itu, hanya bisa ditangkap
bahwa semua cerita ini terjadi dalam cuaca dan suasana
yang rata; dalam kata lain, tiada musim hujan, musim
panas, musim dingin atau apapun.
2) Latar Tempat
Bab satu sampai dengan sembilan terjadi di Solok,
suatu desa di Sumatra, dekat Padang. Daerahnya diduduki
oleh suku Minangkabau dan tidak ramai. Dikatakan bahwa
12
Solok hanya “negeri kecil” di mana semua saling kenal dan
mengurusi urusan tetangga.
Tempat yang lebih spesifik ganti setiap bab. Tempat-
tempat utama dalam kesembilan bab ini adalah rumah Corrie
dan rumah Hanafi. Ada pula satu tempat minor, yaitu di
lapangan tennis.
Latar tempat tidak dideskripsikan secara mendalam.
Pada umumnya teks terfokus pada dialog dan bukan pada
deskripsi. Memang deskripsi hanya terbatas pada satu atau
dua kalimat saja. Contohnya:
“Tempat bermainan tennis, yang dilindungi
oleh pohon-pohon ketapang sekitarnya, masih
sunyi. Cahaya matahari yang diteduhkan oleh
daun-daun di tempat bermain itu, masih keras,
karena dewasa itu baru pukul tengah lima petang
hari (Moeis, 2009: 1).”
Akibatnya, deskripsi tempat tidak dapat dijelaskan
secara mendalam. Latar tempat juga sulit dibayangkan.
3) Latar Sosial Budaya
Latar sosial budaya dalam cerita ini adalah budaya
Minangkabau dalam waktu penjajahan Belanda. Kebudayaan
13
seperti utang budi, kawin paksa, dan mempunyai budak
diwujudkan dalam cerita.
Sebagai akibat dari latar sosial budaya ini ada
beberapa kata daerah yang digunakan dan perlu dijelaskan.
Contohnya, sebutan orang japutan dijelaskan sebagai
berikut: orang berbangsa, jika dia kawin menurut adat
yang biasa, pihak perempuan yang menjemput uang dan lain-
lain.
Kebudayaan lain yang muncul dalam termasuk agama.
Mariam digambarkan sebagai wanita yang heran karena
anaknya tidak punya rasa agama Islam yang kuat, sesuai
dengan pikiran pada saat itu.
Pengaruh dari latar belakang sosial budaya penulis
sangat jelas. Bangsa digambarkan tidak mampu berbaur,
sesuai dengan pikiran umum pada waktu itu. Orang Belanda
pada umumnya digambarkan secara positif, sesuai dengan
kewajiban sensor.
D. Penokohan
Dalam bab satu sampai sembilan ada lima tokoh utama
yang muncul. Dari kelimat tokoh utama ini, yang paling
pokok ada dua. Berikut adalah analisis penokohan tokoh-
tokoh utama, mulai dari kedua tokoh pokok.
14
1) Hanafi
Tokoh utama pertama adalah Hanafi, yang juga
merupakan tokoh protagonis sekalian antagonis cerita ini.
Dia adalah anak yatim bangsa Minangkabau yang pernah
bersekolah di Betawi dan tinggal dengan keluarga Belanda.
Dengan pendidikan dan kebiasaan itu, Hanafi merasa lebih
seperti orang Belanda daripada orang Minangkabau, hingga
pakaian dan bahasanya pun seperti orang Belanda (Moeis,
2009: 24 – 29); oleh karena itu, dia merasa berpangkat
lebih tinggi daripada orang-orang Pribumi lain dan malu
disebut Pribumi (Moeis, 2009: 3).
Walaupun dia cinta pada ibunya, dia amat benci
budaya Minangkabau. Ini terbukti dengan pernyataannya
seperti “negeri Minangkabau sungguh indah, hanya sayang
sekali penduduknya si Minangkabau.” Kebudayaannya, di
antara lain utang budi, kawin paksa, dan dowry (Moeis,
2009: 26 – 32).
Hanafi dan Corrie Du Busée sudah berteman sejak masa
dini. Namun, setelah beberapa tahun rasa cinta telah
timbul dalam hati Hanafi dan akhirnya mereka bercium-
ciuman di depan rumah Hanafi (Moeis, 2009: 46 – 47).
Setelah Corrie Du Busée melarikan diri karena merasa
bersalah, hatinya patah dan dia menjadi tertutup dan
sakit (Moeis, 2009: 59 – 60).
15
Pada bab delapan, Hanafi dinikahkan dengan Rapiah,
anak dari mamaknya. Pernikahan paksa ini membuat Hanafi
semakin kasar, hingga ia ditinggal oleh teman-teman
Belandanya. Dia tidak dapat mengindahkan istrinya ataupun
menganggap dia sebagai ada, walaupun dalam budaya Belanda
perempuan bukanlah budak lelaki. Malahan dia marah kepada
Rapiah setiap ada kesempatan dan tidak mengakui dia
ataupun anak mereka (Moeis, 2009: 79 – 96).
2) Corrie Du Busée
Corrie Du Busée (selanjutnya disebut Corrie) adalah
putri campuran Prancis dan Pribumi yang berusia sembilan
belas tahun. Pada awal cerita ibunya sudah meninggal dan
ayahnya sudah pensiun. Dia bersekolah di Betawi dan
ketika cerita mulai dia pakansi dari sekolah (Moeis,
2009: 1 – 13).
Walaupun dia campuran Pribumi dengan Prancis, Corrie
tidak mengaku budaya ibunya. Ketika bicarakan dirinya dia
selalu menegaskan kebaratannya, biasanya sebagai orang
Belanda. Ketika bergaul dengan orang Pribumi, dia merasa
dirinya lebih penting dan menomorduakan mereka (Moeis,
2009: 1 – 15).
Pikiran Corrie pada umumnya tidak teratur secara
logis dan kurang tegas. Setelah Hanafi mengakui bahwa dia
16
mencintainya, Corrie tidak bisa tidur semalaman dan
mencari-cari bukti bahwa dia tidak merasa apa-apa untuk
Hanafi. Dia menghitung batu, menghitung daun di bunga,
sampai menghitung bunyi toket tetapi selalu tidak setuju
dengan hitungan itu. Akhirnya dia bohong diri terus
(Moeis, 2009: 34 – 40).
Corrie juga seseorang yang mudah terbawa emosi. Saat
pembantunya tidak cukup cepat sediakan minuman, dia marah
dan bersikap keras. Juga, ketika mendadak dicium oleh
Hanafi, dia balas dengan sebirahi-birahinya. Setelah itu,
dia merasa bersalah dan putuskan semua hubungan dengan
Hanafi dan kota Solok; dia melarikan diri ke Betawi
(Moeis, 2009: 46 – 52).
3) Mariam
Mariam adalah ibu dari Hanafi. Dia orang desa totok
dari bangsa Minangkabau yang tidak berpendidikan. Dia
sangat sederhana dalam perilakunya dan tidak suka hal-hal
yang asing baginya. Dia juga takut pada orang-orang
Belanda (Moeis, 2009: 24 – 33).
Mariam merasa sangat berutang kepada Sutan Batuah,
ayah dari Rapiah, karena ia telah membantu dengan
pembayaran sekolah Hanafi. Utang itu merupakan utang uang
17
dan utang budi; oleh karena utang budi ini, Mariam ingin
Hanafi menikah dengan Rapiah (Moeis, 2009: 24 – 33).
Dia bersifat sabar dengan Hanafi dan kekerasannya.
Ketika Hanafi bicara buruk tentang budaya Minangkabau dan
orang-orang di sekitarnya, Mariam sabar mengingatkan dia
atas hidup baik. Dia tidak bersifat marah sama sekali dan
terus memberi nasihat tulus (Moeis, 2009: 24 – 33).
4) Tuan Du Busée
Tuan Du Busée adalah ayah dari Corrie Du Busée. Dia
orang Prancis yang pindah ke Solok, menikah orang lokal,
dan berkeluarga. Walau dulu dia seorang arsitek, pada
awal cerita dia sudah pensiun dan senang habiskan waktu
luang dengan memburu harimau (Moeis, 2009: 10 – 11).
Penokohan Tuan Du Busée tidak begitu dijelaskan;
hanya dua sifat dijelaskan, yaitu bahwa dia tidak peduli
pada warga-warga di luar keluarganya sendiri dan bersifat
sabar dengan putrinya. Ketidakpeduliannya kepada dunia
luar disebabkan karena istrinya diasingkan oleh kawan-
kawan Belanda (Moeis, 2009: 10 – 13). Akhirnya, dia hanya
akrab dengan Corrie dan karena itu mengizinkan dia
lakukan hampir apa saja (Moeis, 2009: 48 - 53).
Oleh karena pengalamannya dengan istri, Tuan Du
Busée sangat ketat tentang hubungan mesra di antara suku
18
Eropa dan Pribumi. Oleh karena itu, dia menjelaskan
kesulitan hubungan romantis antar-etnis kepada Corrie
ketika ditanya apakah hubungan sejenis itu boleh atau
tidak (Moeis, 2009: 18 – 22)
5) Rapiah
Rapiah adalah anak dari Sutan Batuah. Dia anak
kampung yang tidak berpendidikan tinggi. Dia
diperkenalkan dalam bab delapan dan dijodohkan dengan
Hanafi. Dari pernikahan itu dia melahirkan satu anak,
yaitu Syafei (Moeis, 2009: 75 – 81).
Rapiah sangat cinta pada Hanafi, tetapi sudah mulai
putus asa karena dibuang-buangnya. Akhirnya dia menjadi
akrab dengan Mariam dan berusaha keras mengurus rumah
tangga supaya tidak dimarahkan. Ketika dia dimarahkan dia
tinggal hanya sabar (Moeis, 2009: 120 – 128).
19
BAB III: ANALISIS POSKOLONIAL
Hubungan di antara Hanafi, Corrie dan Rapiah dapat
dipandang sebagai analogi keadaan Indonesia pada saat
itu. Hanafi mewakili budaya dan bangsa Indonesia, yang
telah lama dididik oleh kaum asing. Corrie mewakili
budaya Belanda yang asing dan menarik bagi kaum
Indonesia; bisa dikatakan menggoda hati orang Indonesia.
Sedangkan, Rapiah mewakili tradisi dan adat yang sudah
berada di Indonesia beratus tahun.
Oleh karena ada analogi itu, cerita Salah Asuhan
menjadi bukan hanya suatu novel hiburan, tetapi juga
panggilan untuk rakyat Indonesia agar tidak meninggalkan
budaya lama dan berpura-pura Eropa. Masa Hanafi
bersekolah sebelum cerita mulai mewakili zaman penjajahan
Belanda, yang sampai saat itu masih kuat. Hanafi mendapat
ide dan filsafat asing yang membuatnya tidak cocok dengan
asal usulnya.
Masa Hanafi pendekatan dengan Corrie mencerminkan
bagaimana bangsa Indonesia mencoba mengikuti cara hidup
Barat; mendirikan surat kabar, mendirikan sistem
demokratis, hingga menggunakan teknologi seperti sepeda
20
dan mobil. Dengan percobaannya untuk mengistrikan Corrie,
Hanafi menjadi bagai bangsa Indonesia coba mendapatkan
hak yang sama dengan bangsa Eropa.
Namun, harapan itu dihancurkan ketika Corrie
melarikan diri setelah mereka bermesraan; dalam analogi
ini, ketidakinginan Belanda untuk memberi hak asasi ke
bangsa Pribumi. Alasannya sudah dijelaskan oleh Tuan Du
Busée dalam pembicaraannya dengan Corrie: Barat adalah
Barat, Timur adalah Timur, dan kapan pun keduanya
dicampur tiada hasil baik. Orang (negara) lain
meninggalkannya, hingga ditinggal sendiri dengan
pasangannya.
Oleh karena amat kecewa dengan perilaku Corrie,
Hanafi mulai sakit hingga akhirnya rela dijodohkan dengan
Rapiah. Hubungan suami-istri ini mencerminkan kedudukan
budaya tradisional dalam kaum orang yang berpendidikan
Belanda; tradisi-tradisi hanya dipegang karena terpaksa,
tetapi tidak dipercayai ataupun disayangi. Ini
menimbulkan rasa marah dan kecewa dengan budayanya
sendiri, seperti perasaan Hanafi terhadap Rapiah.
BAB IV: PENUTUP
Secara struktural Salah Asuhan tidak istimewa. Ada
tokoh yang utama, ada tokoh minor, ada latar, dan ada
21
narasi. Narasinya dilakukan dengan mendalam pada pikiran
tokoh utama dan penokohan dikembangkan dengan dialog.
Namun, sebagai suatu analogi hubungan Indonesia-
Belanda salah asuhan bersifat luar biasa. Walaupun di
bawah sensor penguasa, Moeis mampu menyampaikan harapan
agar bangsa Indonesia memeluk adat-istadat sendiri dan
tidak berubah menjadi bangsa lain.
Oleh karena kemampuan dan keberanian Abdoel Moeis
itu Salah Asuhan patut dibaca berkali-kali dan diartikan
sebagai perjuangan rahasia bangsa Indonesia. Apalagi,
pesan dalam novel ini agar tidak berubah menjadi yang
bukan-bukan sangat penting kala kini karena globalisasi
dan kehilangan kebudayaan tradisional.
22