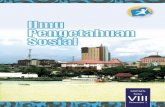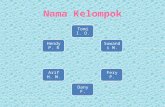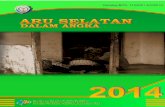analisis perilaku pengobatan penduduk miskin dikabupaten ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of analisis perilaku pengobatan penduduk miskin dikabupaten ...
ANALISIS PERILAKU PENGOBATAN PENDUDUK MISKIN DIKABUPATEN MAJENE
ANALYSIS OF THE MEDICATION BEHAVIOR OF POOR PEOPLE IN MAJENE REGENCY
ANDI ISHAK
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR 2007
ii
ANALISIS PERILAKU PENGOBATAN PENDUDUK MISKIN DIKABUPATEN MAJENE
Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Disusun dan diajukan oleh
ANDI ISHAK
kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007
iii
T E S I S
ANALISIS PERILAKU PENGOBATAN PENDUDUK MISKIN
DIKABUPATEN MAJENE
Disusun dan diajukan oleh
ANDI ISHAK
Nomor Pokok : P03 06 204 506
Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 31 Mei 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Menyetujui
Komisi Penasihat
Prof. Dr. M. Tahir Kasnawi, SU Ketua
Dr. M.M Papayungan, MA Anggota
Ketua Program Studi
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dr. Ir. Didi Rukmana, M.Sc
Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Hasanuddin
Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc
iv
PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ANDI ISHAK
Nomor Pokok : P03 06 204 506
Program Studi : Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)
Konsentrasi Studi Perencanaan Kependudukan
dan Sumber Daya Manusia (SDM)
Judul Tesis : Analisis Perilaku Pengobatan Penduduk Miskin
DiKabupaten Majene
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang tersebut diatas adalah
betul-betul disusun oleh penulis sendiri tanpa disadur/dijiplak dari tesis yang
ada.
Demikian pernyataan ini, penulis buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Makassar, 31 Mei 2007 Yang Menyatakan
ANDI ISHAK
v
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan
tesisi ini tepat waktu.
Dengan terselesaikannya tesis ini penulis menyampaikan terima kasih
yang sebesar – besarnya kepada Bapak Prof. Dr. M. Tahir Kasnawi, SU dan
Bapak Dr. M.M. Papayungan, MA sebagai komisi penasihat yang telah
bersedia menjadi pembimbing dari penyusunan proposal penelitian sampai
pada tahap penyelesaian tesis ini.
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada yang
terhormat Bapak Prof. Dr. Sulaiman Asang. MS, Dr. Paulus Uppun, MA., Dr.dr.
Tahir Abdullah, MPH sebagai Tim Penguji / Penilai , dan juga kami ucapkan
terima kasih kepada Bapak Drs. Johny Anwar , H. Darwis, SE dan ibu Dina
Srikandi, S.ST serta seluruh rekan - rekan kerja atas dukungan moril dan
berbagai saran dalam penyusunan tesis ini.
Akhirnya dengan tulus ikhlas serta iringan doa penulis khaturkan
penghargaan dan terima kasih juga kepada kedua orang tua & Mertua serta
istri tercinta - Enny. B dan ketiga anak – anakku yang tersayang A. Jenyta, A.
Dicky dan A. Felysia atas do’anya sehingga penulisan tesis ini dapat selesai
tepat pada waktunya.
Makassar, M e i 2007
Penulis,
vi
ABSTRAK
ANDI ISHAK. Analisis Perilaku Pengobatan Penduduk Miskin di
Kabupaten Majene dibimbing oleh M.Tahir Kasnawi dan M.M Papayungan
Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui perilaku pengobatan penduduk
miskin yang mempunyai gangguan kesehatan di kabupaten Majene pada
tahun 2005, (2) Menjelaskan pengaruh faktor sosial demografi dan
kecenderungan dari setiap faktor yang mempengaruhi perilaku pengobatan
penduduk miskin yang mempunyai keluhan kesehatan di kabupaten Majene
pada tahun 2005.
Penelitian ini menggunakan data sekunder hasil Survey Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas) Kabupaten Majene tahun 2005 yang dilakukan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan ukuran sampel sebanyak 608
rumah tangga. Data dianalisis dengan teknik tabulasi silang dan regresi
logistik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 49337 penduduk miskin di
Majene terdapat 14,42 persen penduduk yang mempunyai keluhan
kesehatan atau menderita sakit dalam satu bulan terakhir. Dari jumlah
tersebut terdapat 56,8 persen penduduk yang tidak berobat pada pelayanan
kesehatan, baik ke puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, dokter,
tenaga kesehatan, poliklinik, maupun rumah sakit pemerintah/swasta,
sedangkan yang berobat pada pelayanan kesehatan sebesar 43,2 persen.
Faktor tingkat pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah
tangga, dan lamanya terganggu aktivitas secara statistik berpengaruh
signifikan terhadap perilaku pengobatan penduduk miskin di Kabupaten
Majene.
vii
ABSTRACT ANDI ISHAK. Analysis of the Medication Behavior of Poor People in Majene Regency. ( supervised by M.Tahir Kasnawi dan M.M Papayungan.
This research aimed to find out (1) medication behavior of poor people
having health problem in Majene Regency in 2005. (2) the influence of demography social factors and the tendency of each factor effecting medication behavior of poor people who had health problem in Majene Regency in 2005.
This research used secondary data obtained through National
Economics Social Survey of Majene Regency in 2005 conducted by Statistics Centre Board. The sample consisted of 608 households. The data were analyzed descriptively using cross tabulation and infererentially using logistic regression analysis.
The results show that from 49.337 poor people in Majene Regency, 14,42 percent of them have health problems or suffer from any diseases in the last one month. There are 56,8 percent of them who do not have any medical treatments at Public Health Centre, Ministrant Public Health Centre, polindes , doctors, paramedics, policlinic, government/private hospital. On the other hand, there are 43,2 percent of them who have medical treatment at health service. Education level of the household head, number of family members, and the length of disturbed activities statistically have a significant influence on medication behaviour of poor people in Majene Regency.
viii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah. 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Batasan Penelitian 7
F. Sistematika Penulisan 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Pelayanan Kesehatan 9
B. Perilaku Pengobatan 10
C. Penduduk Miskin 18
D. Faktor – faktor yang mempengaruhi Perilaku Pengobatan 20
E. Kajian Teori 28
F. Kerangka Pemikiran 29
G. Hipotesis Penelitian 31
H. Definisi Operasional 31
ix
BAB III. METODE PENELITIAN 35
A. Jenis Penelitian dan Sumber Data 35
B. Populasi dan Sampel 35
C. Spesifikasi Model 37
D. Metode Pengumpulan data 38
E. Teknik Analisis 38
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48
A. Perilaku Pengobatan Penduduk Miskin yang mengalami
Gangguan Kesehatan 48
B. Perilaku Pengobatan 49
C. Pengaruh Variabel Sosial Demografi Terhadap Perilaku
Pengobatan Pada Pelayanan Kesehatan 62
BAB V. PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74
Daftar Pustaka 76
Lampiran 80
x
DAFTAR TABEL
Nomor Halaman 1. Pengkategorian variabel yang digunakan dalam
penelitian 46
2 Persentase penduduk miskin yang mempunyai
gangguan kesehatan menurut perilaku pengobatan di Kabupaten Majene tahun 2005
48
3. Persentase penduduk miskin yang mempunyai
gangguan kesehatan berdasarkan pendidikan KRT dan perilaku pengobatan di Kabupaten Majene tahun 2005
50
4. Persentase penduduk miskin yang mempunyai
gangguan kesehatan berdasarkan tipe daerah dan perilaku pengobatan di Kabupaten Majene tahun 2005
52
5. Persentase penduduk miskin yang mempunyai
gangguan kesehatan berdasarkan lama terganggu dan perilaku pengobatan di Kabupaten Majene tahun 2005
53
6. Persentase penduduk miskin yang mempunyai
gangguan kesehatan berdasarkan kartu sehat dan perilaku pengobatan di Kabupaten Majene tahun 2005
55
7. Persentase penduduk miskin yang mempunyai
gangguan kesehatan berdasarkan kelompok umur dan perilaku pengobatan di Kabupaten Majene tahun 2005
57
8. Persentase penduduk miskin yang mempunyai
gangguan kesehatan berdasarkan jumlah ART dan perilaku pengobatan di Kabupaten Majene tahun 2005
59
9. Persentase penduduk miskin yang mempunyai
gangguan kesehatan berdasarkan status pekerjaan KRT dan perilaku pengobatan di Kabupaten Majene tahun 2005
60
10. Persentase penduduk miskin yang mempunyai
gangguan kesehatan berdasarkan jenis kelamin dan perilaku pengobatan di Kabupaten Majene tahun 2005
61
11. Nilai penduga parameter, statistik Uji Wald, dan nilai
signifikansi 65
12. Nilai penduga parameter dan Odd Ratio 70
xi
DAFTAR GAMBAR
nomor halaman 1. Ilustrasi model Anderson tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi penggunaan pelayanan kesehatan 15
2 Kerangka pikir tentang faktor sosial demografi yang
mempengaruhi perilaku pengobatan 30
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kesehatan merupakan hal yang penting, tidak hanya untuk
kesejahteraan setiap individu, akan tetapi lebih penting lagi untuk menjamin
kesinambungan pembangunan bangsa, dengan tujuan untuk menjadi negara
yang maju, mandiri, berkeadilan, sejajar dengan negara-negara maju di
dunia. Kesehatan merupakan suatu investasi kualitas manusia baik fisik
maupun intelektual.
Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari pembangunan nasional, karena kesehatan menyentuh
hampir semua aspek kehidupan manusia. Tujuan jangka panjang
pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai bagian dari kesejahteraan umum
dari tujuan nasional. Gambaran keadaan masyarakat Indonesia dimasa
depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan dirumuskan
sebagai Indonesia sehat 2010, visi Indonesia sehat 2010 adalah mewujudkan
masyarakat, bangsa, dan negara yang ditandai oleh penduduknya hidup
2
dalam lingkungan dan perilaku yang sehat, memliki kemampauan untuk
menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata
serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selain itu
ditingkatkan penyediaan berbagai sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan
obat-obatan (DepKes RI, 2000)
Melalui pembangunan kesehatan diharapkan akan tercapai derajat
kesehatan masyarakat yang lebih baik. Berbagai upaya untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan pemerintah selama
ini, diantaranya memberikan penyuluhan kesehatan pada masyarakat untuk
berperilaku hidup sehat dan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan
umum, seperti puskesmas, posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa,
serta penyediaan fasilitas air bersih (BPS, 2004).
Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak 1997, mengakibatkan
tingginya angka inflasi yang juga berimbas pada menurunnya tingkat
kesehatan masyarakat, hal ini disebabkan turunnya pendapatan dan daya
beli masyarakat serta meningkatnya biaya kesehatan. Sementara itu dalam
waktu yang bersamaan, ditemukan pula banyak sarana pelayanan kesehatan
yang terancam lumpuh. Penyebab utamanya tidak saja karena turunnya
jumlah pengunjung, tetapi juga karena sulitnya memperoleh bahan-bahan
habis pakai serta obat-obatan, yang sebagian besar diantaranya memang
masih sangat tergantung dari impor (Azwar, 1999). Oleh karena itu tanggung
3
jawab pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
semakin berat.
Pada tahun 2000 Human Development Indeks (HDI) Indonesia telah
mencapai peringkat 102 dari 190 negara di dunia. Di tahun 2003 peringkat
Indonesia merosot menjadi 112, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan
kesehatan Indonesia jauh dari memuaskan (Dyas, 2004).
Kemiskinan dapat mengancam status kesehatan dengan
meningkatnya angka kesakitan penduduk miskin yang disebabkan oleh
menurunnya akses masyarakat ke pengetahuan dan informasi, serta
rendahnya kemampuan untuk mengakses ke pelayanan kesehatan. Selain itu
kemiskinan juga menyebabkan meningkatnya faktor resiko personal dan
lingkungan yang dapat meningkatkan kesakitan.
Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua
lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah
dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat
kesehatan masyarakat yang lebih baik. Salah satu indikator yang digunakan
untuk memantau derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan
(morbidity rate). Survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2005 menunjukkan
bahwa penduduk miskin di Majene yang mengalami gangguan kesehatan
selama sebulan yang lalu sebesar 14,42 persen. Gangguan kesehatan yang
banyak diderita oleh masyarakat Majene adalah panas (6,12 persen), batuk
4
(5,10 persen), dan pilek (4,61 persen). Dari seluruh penduduk miskin di
Majene yang mengalami gangguan kesehatan selama sebulan yang lalu
persentase penduduk miskin yang berobat pada pelayanan kesehatan
kurang dari 50 persen yaitu sebesar 43,2 persen sementara berdasarkan
Statistik Kesehatan Majene Dalam Angka Tahun 2005 jumlah sarana
pelayanan kesehatan di Majene terdiri dari: 1 rumah sakit umum, 7
puskesmas, 33 puskesmas pembantu, 32 puskesmas keliling, 9 praktek
dokter umum dan 175 posyandu. Jumlah tenaga kesehatan yang ada, terdiri
dari: 12 dokter umum, 5 dokter gigi, 2 dokter ahli, dan 235 tenaga paramedis
yang tersebar di kabupaten Majene, dengan demikian kontak masyarakat
Majene dengan fasilitas kesehatan umumnya masih relatif rendah.
Pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah salah satu bentuk nyata
untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dengan
memanfaatkan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan baik oleh
pemerintah maupun swasta, berarti menurunnya angka kesakitan dan akan
tercipta masyarakat yang sehat sehingga akan menghasilkan sumber daya
manusia yang cerdas dan produktif (Yuliawati, 2002).
Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendekatkan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dalam rangka
meningkatkan pemerataan akses ke pelayanan kesehatan dan menurunkan
angka gangguan sakit, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut
5
tentang perilaku pengobatan penduduk miskin di Majene pada tahun 2005
dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
B. Rumusan Masalah
Sasaran pembangunan kesehatan dimasa mendatang adalah
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta keterjangkauan sarana
pelayanan kesehatan oleh masyarakat miskin. Dengan demikian diharapkan
masyarakat, terutama masyarakat miskin di daerah pedesaan serta daerah-
daerah terpencil dapat menggunakan sarana pelayanan kesehatan.
Fenomena yang terjadi di Kabupaten Majene bahwa pemanfaatan pelayanan
kesehatan oleh penduduk relatif masih rendah dan jumlah penduduk miskin
yang relatif tinggi. Dengan demikian, beberapa permasalahan yang dihadapi
dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana karakteristik faktor sosial demografi yang dapat
mempengaruhi perilaku pengobatan penduduk miskin yang mengalami
gangguan kesehatan pada pelayanan kesehatan di Kabupaten Majene
pada tahun 2005 ?
2. Bagaimana peranan faktor sosial demografi yang paling cenderung
dalam mempengaruhi perilaku pengobatan penduduk miskin yang
mengalami gangguan kesehatan pada pelayanan kesehatan di
Kabupaten Majene pada tahun 2005 ?
6
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pemanfaatan pelayanan
kesehatan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
yang akan mendukung pembangunan nasional maupun daerah dengan
menggunakan data sosial demografi dari hasil Survei Sosial Ekonomi
Nasional tahun 2005 di Kabupaten Majene.
Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan
penelitian ini adalah:
1. Mengetahui karakteristik faktor sosial demografi yang dapat
mempengaruhi perilaku pengobatan penduduk miskin yang mengalami
gangguan kesehatan pada pelayanan kesehatan di Kabupaten Majene
pada tahun 2005.
2. Mengetahui kecenderungan peranan faktor sosial demografi dalam
mempengaruhi perilaku pengobatan penduduk miskin yang mengalami
gangguan kesehatan pada pelayanan kesehatan di Kabupaten Majene
pada tahun 2005.
D. Kegunaan Penelitian
Kebijakan Pembangunan Nasional dan Otonomi Daerah telah
membawa perubahan strategik pada peningkatan kualitas penduduk.
Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mewujudkan kualitas penduduk yang
7
sehat, namun demikian peningkatan taraf kesehatan penduduk, terutama
penduduk yang miskin merupakan tanggung jawab semua pihak.
Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian
ini adalah :
1. Menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dalam penetapan
kebijakan serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
masalah kependudukan terutama dalam upaya penanggulangan
kemiskinan khususnya di Kabupaten Majene.
2. Dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di
bidang kependudukan, peningkatan kesehatan masyarakat dan dapat
menjadi referensi bagi yang berminat terhadap masalah
kependudukan, peningkatan kesehatan masyarakat khususnya
penanggulangan masyarakat miskin.
E. Batasan Penelitian
Dalam penulisan ini permasalahan perilaku pengobatan yang dibahas
dibatasi untuk Kabupaten Majene pada tahun 2005. Analisis deskriptif dan
analisis regresi logistik yang dilakukan terbatas dengan menggunakan faktor
sosial demografi tahun 2005 yang dapat menggambarkan keterkaitannya
dengan perilaku pengobatan penduduk miskin di Kabupaten Majene pada
tahun 2005 adalah : pendidikan kepala rumah tangga, status pekerjaan
8
kepala rumah tangga, tipologi daerah perkotaan dan pedesaan, kepemilikan
kartu sehat, jumlah anggota rumah tangga, jenis kelamin anggota rumah
tangga yang mengalami gangguan kesehatan, umur anggota rumah tangga
yang mengalami gangguan kesehatan, dan lama terganggu aktifitas karena
mengalami gangguan kesehatan.
F. Sistematika Penulisan
Penulisan tesis ini dibagi kedalam lima bab sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang tinjauan pustaka, kajian teori,
kerangka teori, hipotesis penelitian, dan defenisi operasional.
Bab III : Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian dan sumber data,
populasi dan sampel, spesifikasi model, metode pengumpulan
data, dan teknik analisis.
Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang gambaran perilaku
pengobatan penduduk miskin yang mempunyai gangguan
kesehatan dan faktor sosial demografi yang mempengaruhi
perilaku pengobatan penduduk miskin yang mempunyai gangguan
kesehatan.
Bab V : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan
secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara
dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta
memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun
masyarakat (Levey&Loomba (Yulianingsih, 2001)).
Lumenta (Yuliawati, 2002) mendefinisikan pelayanan kesehatan
sebagai upaya dan kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit, semua
upaya dan kegiatan peningkatan akan pemulihan kesehatan yang dilakukan
pranata sosial atau pranata politik terhadap keseluruhan masyarakat sebagai
tujuannya. Pelayanan kesehatan ialah suatu kegiatan makrososial yang
berlaku antara pranata atau lembaga dengan populasi tertentu, masyarakat
atau komunitas.
Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan
sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta yang
penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang
ditetapkan (Azwar, 1993).
10
B. Perilaku Pengobatan pada Pelayanan Kesehatan
Perilaku adalah apa yang dikerjakan oleh organisme, baik secara
langsung ataupun yang dapat diamati secara tidak langsung. Robert Kick
(Nandipinta, 2000) menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau
perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari.
Menurut Notoatmodjo (Nandipinta, 2000) bahwa perilaku kesehatan
pada dasarnya adalah respon seseorang (organisme) terhadap stimulus yang
berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan
serta lingkungan. Secara lebih rinci perilaku kesehatan tersebut mencakup
beberapa hal sebagai berikut:
1. Perilaku seseorang terhadap sakit dan penyakit, yaitu bagaimana
manusia merespon, baik secara pasif (mengetahui, bersikap, dan
mempersepsikan tentang penyakit dan rasa sakit yang ada pada
dirinya dan luar dirinya, maupun aktif (tindakan yang dilakukan
sehubungan dengan penyakit dan sakit tersebut.
2. Perilaku terhadap sistem pelayanan kesehatan, adalah respon
seseorang terhadap sistem pelayanan kesehatan, baik sistem
pelayanan kesehatan modern maupun tradisional. Perilaku ini
menyangkut respon terhadap fasilitas pelayanan, cara pelayanan,
petugas kesehatan, dan obat-obatannya yang terwujud dalam
11
pengetahuan, persepsi, sikap dan penggunaan fasilitas, petugas dan
obat-obatan.
3. Perilaku terhadap makanan, adalah respon seseorang terhadap
makanan sebagai kebutuhan vital bagi kehidupan. Perilaku ini meliputi
pengetahuan, persepsi, sikap dan praktek terhadap makanan serta
unsur-unsur yang terkandung di dalamnya (zat gizi), pengelolaan
makanan, dan sebagainya sehubungan kebutuhan tubuh kita.
4. Perilaku terhadap lingkungan kesehatan, adalah respon seseorang
terhadap lingkungan sebagi determinan kesehatan manusia.
Sedangkan Becker (Nandipinta, 2000) mengklasifikasikan perilaku
yang berhubungan dengan kesehatan sebagai berikut:
1. Perilaku kesehatan (Health Behavior), yaitu hal-hal yang berkaitan
dengan tindakan seseorang dalam memelihara dan meningkatkan
kesehatannya, termasuk juga tindakan-tindakan untuk mencegah
penyakit, kebersihan perseorangan, memilih makanan, sanitasi dan
sebagainya.
2. Perilaku sakit (Illnes Behavior), yaitu segala tindakan atau kegiatan
yang dilakukan oleh seseorang individu yang merasa sakit, untuk
merasakan dan mengenal keadaan kesehatannya atau rasa sakit,
termasuk juga kemampuan atau pengetahuan individu untuk
12
mengidentifikasi penyakit, penyebab penyakit, serta usaha-usaha
mencegah penyakit tersebut.
3. Perilaku peran sakit (Sick role behavior), yaitu segala tindakan atau
kegiatan yang dilakukan oleh individu yang sedang sakit untuk
memperoleh kesembuhan. Perilaku ini disamping berpengaruh
terhadap kesehatan/kesakitannya sendiri, juga berpengaruh terhadap
orang lain.
Menurut Notoatmodjo (Herlina, 2001) ada 6 (enam) perilaku
sehubungan dengan perilaku pengobatan, yaitu:
1. Tidak bertindak apa-apa (no action), alasannya antara lain bahwa
kondisi yang demikian tidak mengganggu kegiatan atau kerja mereka
sehari-hari. Mungkin mereka beranggapan bahwa tanpa tindakan
apapun gejala yang dideritanya akan lenyap dengan sendirinya.
2. Bertindak mengobati sendiri (self treatment), alasannya karena orang
tersebut sudah percaya kepada diri sendiri, dan sudah merasa bahwa
berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu usaha-usaha
pengobatan sendiri sudah dapat mendatangkan kesembuhan,
sehingga pencarian pengobatan keluar tidak diperlukan.
3. Mencari pengobatan ke fasilitas-fasilitas pengobatan tradisional
(traditional remedy). Pada masyarakat yang masih sederhana,
13
masalah sehat-sakit adalah lebih bersifat budaya dari gangguan-
gangguan fisik. Identik dengan itu pencarian pengobatan pun lebih
berorientasi pada sosial budaya masyarakat daripada hal-hal yang
dianggapnya masih asing.
4. Mencari pengobatan dengan membeli obat ke warung-warung obat
dan sejenisnya, termasuk ke tukang-tukang jamu.
5. Mencari pengobatan ke fasilitas-fasilitas pengobatan modern yang
diadakan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga kesehatan swasta,
yang dikategorikan ke dalam balai pengobatan, puskesmas dan rumah
sakit.
6. Mencari pengobatan ke fasilitas pengobatan modern yang
diselenggarakan oleh dokter praktek swasta.
Dari uraian tersebut di atas tampak jelas bahwa persepsi masyarakat
terhadap sehat-sakit adalah berbeda dengan konsep sehat-sakit dari
pelayanan kesehatan. Demikian pula persepsi sehat-sakit antara kelompok-
kelompok masyarakat pun akan berbeda-beda pula. Persepsi masyarakat
terhadap sehat-sakit sangat erat hubungannya dengan perilaku pengobatan.
Wolansky (Yulianingsih, 1999) menyatakan bahwa pemanfaatan
pelayanan kesehatan pada diri seseorang untuk melawan atau mengobati
melibatkan empat variabel kunci, yaitu:
14
1. Kerentanan terhadap apa yang dirasakan (Perceived susceptibility),
agar seseorang bertindak untuk mengobati atau mencegah
penyakitnya, ia harus merasakan bahaya dan menyadari bahwa ia
rentan terhadap penyakit. Tindakan pencegahan terhadap suatu
penyakit akan timbul bila seseorang telah merasakan bahwa ia rentan
terhadap penyakit.
2. Keseriusan yang dirasakan (perceived seriousness), tindakan individu
untuk mencari pengobatan dan mencegah penyakit yang didorong
oleh keseriusan penyakit tersebut terhadap individu maupun
masyarakat.
3. keuntungan yang dirasakan dan hambatan-hambatan (perceived
benefits and barriers), apabila individu merasakan dirinya rentan
terhadap penyakit-penyakit yang dianggap gawat atau serius, ia akan
melakukan tindakan tertentu. Tindakan tersebut tergantung pada
keuntungan-keuntungan yang akan dirasakan dan hambatan-
hambatan yang akan dialaminya, pada umumnya keuntungan tindakan
lebih menentukan daripada hambatan yang mungkin timbul.
4. Isyarat atau tanda-tanda (Cuess), untuk mendapatkan tingkat
penerimaan yang benar tentang kerentanan, kegawatan, dan
keuntungan tindakan, maka diperlukan isyarat berupa faktor-faktor luar
15
seperti pesan dari media massa, nasehat kawan maupun anggota
keluarga.
Untuk mengetahui keputusan seseorang dalam memanfaatkan
pelayanan kesehatan dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1. Ilustrasi model Anderson tentang faktor - faktor yang mempengaruhi penggunaan pelayanan kesehatan
Dari gambar 1 di atas perilaku penggunaan pelayanan kesehatan
dapat dikelompokkan dalam tiga faktor utama yang mempengaruhi terhadap
pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:
1. Faktor predisposisi (Predisposing factor), digunakan untuk
menggambarkan fakta bahwa setiap individu mempunyai
kecenderungan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang berbeda-
beda, digolongkan dalam tiga kelompok yaitu, ciri demografi seperti
jenis kelamin, umur, struktur sosial seperti tingkat pendidikan,
pekerjaan, suku dan ras. Ciri kepercayaan kesehatan (helth believe)
Predisposisi
Pendukung Kebutuhan Penggunaan Pelayanan Kesehatan
? Demografi ? Struktur Sosial ? Kepercayaan
Kesehatan
? Sumber Daya Keluarga
? Sumber Daya Masyarakat
Persepsi Evaluasi
16
seperti keyakinan pada pelayanan kesehatan untuk dapat menolong
proses penyembuhan penyakit, sikap individu atau orang memiliki
perbedaan karakteristik, perbedaan tipe, dan frekuensi penyakit, juga
perbedaan pola penggunaan pelayanan kesehatan.
2. Faktor pendukung atau pemungkinan (Enabling factor), mencerminkan
bahwa meskipun mempunyai predisposisi untuk menggunakan
pelayanan kesehatan, seseorang tidak akan menggunakannya.
Penggunaan pelayanan kesehatan tergantung kemampuan konsumen
untuk membayar. Faktor pemungkin meliputi lingkungan fisik
(mencakup) ketersediaan fasilitas dan ketercapaian fasilitas.
3. Faktor kebutuhan (need factor), faktor predisposisi dan faktor yang
mendukung untuk mencari pengobatan dapat terwujud dalam tindakan
bila dirasakan sebagai kebutuhan sehingga kebutuhan merupakan
stimulus langsung untuk menggunakan pelayanan kesehatan. Faktor
kebutuhan (need) dibagi dalam 2 kategori yaitu kebutuhan yang
dirasakan (subjectif assessment) dan teruji (clinical diagnosis).
Model lain yang dikemukakan oleh Wolansky (Herlina, 2001) yaitu
model pendekatan dalam penelitian untuk menmpengaruhi faktor-faktor yang
mempengaruhi tindakan untuk berobat antara lain adalah:
17
1. Model demografi (Demografic model), variabel yang digunakan yaitu
umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan besarnya keluarga.
Perbedaan derajat kesehatan sedikit banyak akan dipengaruhi oleh
variabel di atas, ciri-ciri demografi tersebut adalah cerminan atau
berhubungan dengan ciri-ciri sosial.
2. Model struktur sosial (social structure models), dalam hal ini variabel
yang digunakan adalah pendidikan, pekerjaan, dan kesukuan atau
kebangsaan. Variabel ini mencerminkan porsi sosial individu atau
keluarga di dalam masyarakat, penggunaan pelayanan kesehatan
adalah salah satu aspek dari gaya hidup orang, yang ditentukan oleh
lingkungan fisik, sosial, dan psikologis.
3. Model sosial psikologis (social psychological models), pada model ini
variabel yang digunakan adalah sikap dan keyakinan individu. Variabel
sosial psikologis ini terdiri dari 4 kategori yaitu:
? Kerentanan terhadap penyakit atau sakit
? Menerima keseriusan penyakit atau sakit
? Keuntungan yang diharapkan dalam mengambil tindakan untuk
mengatasi penyakit atau sakit
? Kesiapan tindakan individu
4. Model sumber keluarga (family resource model), variabel yang
digunakan adalah pendapatan, asuransi di dalam keluarga.
18
C. Penduduk Miskin
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis
Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang
berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap (tinggal)
lebih dari enam bulan (BPS, 2000).
Miskin adalah tidak berharta benda, atau serba kekurangan
(berpenghasilan sangat rendah), sedangkan kemiskinan adalah keadaan
miskin absolute, situasi penduduk atau sebagian penduduk yang tidak dapat
memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan perumahan yang diperlukan
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994).
Menurut Bank Dunia (World Bank, 2000), “poverty is a pronounced
deprivation in well being” (kemiskinan dinyatakan sebagai tidak adanya
kesempatan meraih kesejahteraan), dimana kesejahteraan dapat diukur oleh
kekayaan yang dimiliki seseorang, kesehatan, gizi, pendidikan, asset,
perumahan dan hak-hak tertentu dalam masyarakat seperti kebebasan
berbicara. Kemiskinan juga merupakan kurangnya kesempatan/peluang,
ketidakberdayaan, serta kerentanan dalam bidang ekonomi, pendidikan,
kesehatan, ketenagakerjaan, dan sebagainya. Kemiskinan benar-benar
merupakan masalah multidimensi yang memerlukan kebijakan dan program
19
intervensi pula agar kesejahteraan individu meningkat sehingga membuatnya
terbebas dari kemiskinan.
Quibria (Budiantini, 2003) mengemukakan bahwa ada dua istilah
umum yang digunakan dalam mengartikan kemiskinan, yaitu kemiskinan
absolute dan kemiskinan relatif. Seseorang dikategorikan miskin secara
absolute apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis
kemiskinan absolute yang telah ditetapkan, dengan kata lain jumlah
pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang
dicerminkan oleh garis kemiskinan absolute tersebut. Kemiskinan relatif
adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam
masyarakat, yakni antar kelompok yang mungkin tidak miskin karena
mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan
kelompok masyarakat relatif lebih kaya.
Kemiskinan merupakan kondisi kehidupan yang serba kekurangan
yang dialami seseorang yang pengeluaran per kapitanya selama sebulan
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Kebutuhan
standar hidup minimum digambarkan dengan garis kemiskinan (GK), yaitu
batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan
minimum makanan dan non makanan. Batas kecukupan minimum makanan
mengacu pada Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi pada tahun 1978,
yaitu besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk makanan yang memenuhi
20
kebutuhan minimum energi 2100 kalori per hari, sedangkan kebutuhan
minimum non makanan mencakup pengeluaran untuk perumahan,
penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi,
barang-barang tahan lama serta barang dan jasa esensial lainnya. Jumlah
orang miskin/head count index (HCI) dapat dilihat melalui jumlah orang yang
berada di bawah atau sama dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan
Kabupaten Majene yang dibuat BPS adalah Rp.107.309/kap/bulan.
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pengobatan
Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengobatan pada
pelayanan kesehatan terdiri atas:
1. Pendidikan
Cara berpikir seseorang, kematangan, intelektual, wawasan dan
bahkan dalam membuat kebijakan biasanya sangat ditentukan dari
pendidikan orang tersebut. Dalam kehidupan manusia pada umumnya tidak
terlepas dari proses pendidikan karena dalam kehidupan manusia itu sendiri
tidak terlepas dari ketergantungan satu dengan yang lainnya. Pendidikan
adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan
pada anak, yang tertuju pada kedewasaan (Notoatmodjo (Herlina, 2001)).
Pendidikan adalah variabel sosial demografi yang sering dihubungkan
dengan perilaku pengobatan pada pelayanan kesehatan. Pendidikan kepala
21
rumah tangga adalah kunci dari ukuran yang digunakan. Kesenjangan untuk
berobat pada pelayanan kesehatan orang berpendidikan rendah dengan
orang berpendidikan menengah, lebih lebar daripada kesenjangan
pemanfaatan kesehatan antara pendidikan menengah dengan pendidikan
tinggi.
Menurut Feldstein (Yulianingsih, 2001) bahwa tingkat pendidikan
dipercaya mempengaruhi permintaan akan pelayanan kesehatan. Pendidikan
yang tinggi memungkinkan seseorang untuk mengetahui atau mengenal
gejala awal dari suatu penyakit, sehingga berkeinginan untuk segera
mendapatkan perawatan. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga akan
sangat menentukan perilaku pengobatan dan pemanfaatan pelayanan
kesehatan manakala anggota keluarga mengalami gangguan sakit.
Orang dengan pendidikan formal lebih tinggi akan mempunyai
pengetahuan yang lebih tinggi dibanding orang dengan pendidikan formal
yang lebih rendah, karena akan lebih mampu dan lebih mudah memahami
arti dan pentingnya kesehatan serta pengobatan pada pelayanan kesehatan.
Notoatmodjo, dkk (Yuliaaningsih, 2001) menyatakan tingkat pendidikan yang
lebih tinggi akan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang canggih. Tingkat
pendidikan mempengaruhi kesadaran akan pentingnya arti kesehatan bagi
diri dan lingkungan yang dapat mendorong kebutuhan akan pelayanan
kesehatan.
22
Penelitian Supriyadi (2004) menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat
pendidikan maka cenderung semakin tinggi penggunaan pelayanan
kesehatan formal, dan semakin rendah penggunaan pelayanan kesehatan
informal.
2. Status Pekerjaan
Seseorang yang bekerja di sektor informal cenderung lebih sering sakit
daripada orang yang bekerja di sektor formal, akan tetapi orang yang bekerja
di sektor formal memiliki akses ke pelayanan rawat jalan yang lebih besar
dibandingkan dengan orang yang bekerja di sektor informal, selain didukung
oleh biaya juga kecenderungan jenis penyakit yang dialami relatif berat.
Dalam teori Wolansky (Herlina, 2001) pekerjaan termasuk faktor yang
mempengaruhi tindakan seseorang untuk berobat yaitu masuk dalam model
struktur sosial, sedangkan Andersen (1975) pekerjaan merupakan faktor
yang memberikan kemudahan/kelancaran di dalam bertindak dalam
menggunakan pelayanan kesehatan.
Berdasarkan BKKBN tahun 1999 terdapat dua jenis pekerjaan yaitu:
1. Pekerjaan non formal, yaitu pekerjaan/bekerja yang tidak terikat
dengan aturan resmi, seperti tani, buruh, dan dagang.
2. Pekerjaan formal, yaitu bekerja yang terikat dengan aturan resmi
seperti karyawan swasta, PNS, TNI/POLRI dan pamong desa.
23
Penelitian Sigit (2004) menyebutkan ada hubungan antara variabel
status pekerjaan ayah dengan pencarian pengobatan bagi balita ISPA.
Senada dengan itu, penelitian Supriyadi (2004) juga menyebutkan ada
hubungan yang bermakna antara pekerjaan kepala keluarga dengan
pemanfaatan pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan dokter lebih banyak
digunakan oleh tenaga manajemen, sedangkan paramedis lebih banyak
digunakan oleh kelompok pekerjaan tenaga kasar.
3. Jumlah Anggota Keluarga
Bossard dan Boll (Yulianingsih, 2001) menyebutkan perbedaan antara
anak yang berada pada keluarga besar dengan pada keluarga kecil, anak
yang berada pada keluarga kecil biasanya mendapatkan perhatian yang lebih
baik dari segi pendidikan, kesejahteraan. Keluarga kecil biasanya lebih
demokratik dan kooperatif.
Penelitian Supriyadi (2004) menyebutkan ada hubungan yang
bermakna antara variabel jumlah anggota keluarga dengan pemanfaatan
pelayanan kesehatan, keluarga dengan jumlah anggota 4-5 orang memiliki
kecenderungan yang lebih tinggi menggunakan pelayanan kesehatan, dan
pengobatan sendiri lebih banyak digunakan oleh keluarga dengan jumlah
anggota 1-3 orang.
24
4. Umur
Menurut Azwar (1988) umur merupakan variabel yang penting dalam
mempelajari suatu masalah kesehatan karena:
1. Ada kaitannya dengan daya tahan tubuh. Pada umumnya daya tahan
tubuh orang dewasa jauh lebih kuat daripada daya tahan bayi atau
anak-anak.
2. Ada kaitannya dengan ancaman terhadap kesehatan. Orang dewasa
karena pekerjaan ada kemungkinan menghadapi ancaman penyakit
lebih besar daripada anak-anak.
Feldstein (Supriyadi, 2004) menyatakan ada hubungan umur,
penghasilan dan pendidikan terhadap aspek kesehatan. Semakin tinggi usia
seseorang maka semakin tinggi frekuensi pemanfaatan pelayanan
kesehatan. Hubungan antara umur dengan pemanfaatan pelayanan medis
berbeda untuk setiap jenis pelayanan.
Penelitian Yuliawati (2002) menyebutkan ada hubungan yang
bermakna antara umur dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan.
Penelitian Supriyadi (2004) juga menyebutkan adanya hubungan yang
bermakna antara umur dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan bahwa
semakin bertambahnya umur maka cenderung semakin tinggi pemanfaatan
pelayanan kesehatan rawat jalan.
25
5. Tipe Daerah
karakteristik wilayah berhubungan dengan penggunaan pelayanan
kesehatan rawat jalan menurut kebutuhan pada individu. Ketidakmerataan
dalam pelayanan kesehatan tercermin dari perbedaan akses di daerah rural
dan urban.
Di negara berkembang, sebagian besar penduduk umumnya tinggal di
daerah pedesaan yang kekurangan sarana pengobatan modern.
Terpencilnya penduduk desa secara fisik memberikan masalah-masalah
serius dalam memperluas pelayanan dan sarana kesehatan dasar,
pertumbuhan penduduk yang cepat di kota-kota negara berkembang
menambah ketidakpedulian dan penundaan penyediaan pelayanan
kesehatan di desa-desa.
Menurut azwar (1985) penyebaran masalah kesehatan menurut
tempat terjadinya amat penting karena keterangan yang diperoleh akan dapat
diketahui beberapa hal yaitu:
1. Jumlah jenis masalah kesehatan yang ditemukan di suatu daerah.
Dengan diketahuinya penyebaran penyakit di suatu daerah dapat
diketahui dengan tepat masalah-masalah kesehatan yang ada di
daerah tersebut.
2. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan di
suatu daerah. Apabila telah diketahui jumlah dan jenis masalah
26
kesehatan, dapat disusun program kesehatan yang tepat untuk daerah
tersebut.
3. keterangan tentang faktor penyebab timbulnya masalah kesehatan ini
dapat diperoleh dengan membandingkan hal-hal khusus yang ada dan
tidak ada pada suatu daerah. Perbedaan hal-hal khusus tersebut
mungkin adalah penyebab masalah kesehatan yang dimaksud.
Keadaan-keadaan khusus yang dimaksud banyak macamnya, yang
terpenting adalah:
a. Keadaan geografis, misalnya letak wilayah, struktur tanah,
curah hujan, kelembaban udara, dan sebagainya.
b. Keadaan penduduk. Perbedaan keadaan penduduk juga
menentukan perbedaan penyebab penyakit menurut tempat,
misalnya jumlah penduduk dan keadaan penduduk.
c. Keadaan pelayanan kesehatan. Keadaan pelayanan kesehatan
di suatu tempat juga mempengaruhi penyebaran penyakit di
tempat itu.
Penelitian Yulianingsih (2001) dan Yuliawati (2002) menyebutkan ada
hubungan yang bermakna antara tipe daerah tempat tinggal dengan
pemanfaatan pelayanan kesehatan.
27
6. Kartu Sehat
Kartu sehat adalah bukti diri yang diberikan kepada keluarga miskin,
yang termasuk dalam program JPSBK, untuk mendapatkan jaminan
pelayanan kesehatan gratis.
Penelitian Nani Rohani (2003) di Kabupaten Bekasi, menunjukkan
bahwa secara umum program JPSBK meningkatkan kunjungan keluarga
miskin ke sarana pelayanan kesehatan. Penelitian Yuliawati (2002)
menyebutkan bahwa penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
(Askes/Astek/Jamsostek, perusahaan/kantor, asuransi lain, dana sehat, kartu
sehat, JPKM) mempunyai peluang memanfaatkan pelayanan kesehatan 1,8
kali dibandingkan yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
7. Jenis Kelamin
Dalam Susenas 2005 jenis kelamin tercatat sebagai laki-laki dan
perempuan. Menurut Azwar (1985) jenis kelamin mempengaruhi perilaku
kesehatan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu:
1. perbedaan anatomi dan fisiologi antara pria dengan wanita.
Contoh tumor prostat yang hanya ditemukan pada kaum pria saja
2. Perbedaan kebiasaan hidup antara wanita dan pria.
Ditemukan banyak penderita kanker paru-paru pada pria antara lain
karena kaum pria lebih banyak yang merokok daripada kaum wanita.
28
3. Perbedaan macam pekerjaan.
Penyakit akibat kerja misalnya lebih banyak ditemukan pada kaum
pria, karena mereka lebih banyak yang bekerja.
Penelitian Supriyadi (2004) menyebutkan bahwa ada hubungan antara
pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan jenis kelamin.
8. Lamanya Terganggu Aktivitas
Lamanya terganggu aktivitas karena menderita sakit (disability day)
berhubungan langsung terhadap perasaan akan seriusnya penyakit yang
dirasakan. Phelp (Yulianingsih, 2001) mengemukakan bahwa jumlah hari
sakit berhubungan positif dengan angka kunjungan ke dokter.
Penelitian Supriyadi (2004) menyebutkan semakin lama hari
terganggu maka pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan cenderung
semakin meningkat. Musaddad et al (1982) menyatakan bahwa faktor-faktor
jarak ke fasilitas kesehatan, pendidikan ibu, keterpaparan terhadap media
massa, dan lama terganggu berperanan penting dalam pengaruhnya
terhadap pencarian pelayanan kesehatan.
E. Kajian Teori
Dari tinjauan pustaka diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku
pengobatan pada pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor;
yaitu: jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, suku, ras,
29
keyakinan pada pelayanan kesehatan untuk dapat menolong proses
penyembuhan penyakit, sikap, ketersediaan fasilitas dan ketercapaian
fasilitas, perbedaan tipe dan frekuensi penyakit, pengeluaran keluarga,
jaminan kesehatan, jarak ke fasilitas kesehatan, pendidikan ibu, keterpaparan
terhadap media massa, dan lama terganggu aktivitas. Faktor sosial demografi
dan ekonomi tersebut selanjutnya disebut sebagai variabel penjelas.
Akan tetapi karena keterbatasan data tidak semua variabel penjelas
dapat diamati. Variabel penjelas di bidang sosial demografi yang diamati
meliputi pendidikan, status pekerjaan, tipe daerah, kartu sehat, jumlah
anggota rumah tangga, jenis kelamin, umur, dan lama tergangu aktivitas.
Sedangkan variabel ekonomi tidak diamati karena unit analisis yang
digunakan adalah penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan,
jelas memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Dalam penelitian ini variabel
respon yang digunakan adalah perilaku pengobatan penduduk miskin yang
mempunyai gangguan kesehatan.
F. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori di atas maka
perilaku pengobatan pada pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh beberapa
variabel, yaitu:
30
Variabel Sosial Variabel Demografi
Gambar 2. Kerangka pikir tentang faktor sosial demografi yang mempengaruhi perilaku pengobatan
Kepemilikan Kartu Sehat
Jumlah Anggota Rumah Tangga Miskin
Jenis Kelamin Penduduk dengan
Gangguan Kesehatan
Umur Penduduk dengan Gangguan
Kesehatan
Lama Terganggu Aktifitas karena
Gangguan Kesehatan
Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga
Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga
Tipologi Daerah Tempat Tinggal
Perilaku Pengobatan Penduduk Miskin
Menggunakan Pelayanan Kesehatan
Tidak Menggunakan Pelayanan Kesehatan
31
Perilaku pengobatan yang terdiri atas berobat dan tidak berobat
sebagai variabel respon/variabel tak bebas dipengaruhi oleh faktor sosial
demografi sebagai variabel penjelas/variabel bebas dimana faktor sosial
terdiri atas Pendidikan KRT, Status Pekerjaan KRT, Tipe Daerah, dan Kartu
Sehat, sedangkan faktor demografi terdiri atas JART (Jumlah Anggota
Rumah Tangga), Jenis Kelamin, dan Umur.
G. Hipotesis Penelitian
Untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan,
maka hipotesa yang akan dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah:
“ Diduga ada pengaruh faktor sosial demografi yaitu pendidikan KRT (Kepala
Rumah Tangga), status pekerjaan KRT, tipe daerah, kartu sehat, jumlah
anggota rumah tangga, jenis kelamin, umur, dan lama terganggu terhadap
perilaku pengobatan penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan
di kabupaten Majene “.
H. Defenisi Operasional
Sebagaimana telah disebutkan bahwa sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Susenas 2005 KOR, maka defenisi operasional
variabel yang dipakai juga akan merujuk pada konsep dan defenisi Badan
Pusat Staistik (BPS).
32
? Variabel respon (Y) adalah perilaku pengobatan penduduk miskin
pada pelayanan kesehatan adalah kegiatan atau upaya penduduk
miskin yang mempunyai gangguan kesehatan untuk memeriksakan diri
dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat
pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap,
termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah.
? Variabel penjelas (X) adalah variabel yang digunakan untuk
memprediksi variabel respon. Variabel penjelas yang digunakan disini
adalah variabel dalam faktor sosial demografi yang berhubungan
dengan perilaku pengobatan pada pelayanan kesehatan, yaitu:
1. Pendidikan Kepala Rumah Tangga adalah pendidikan formal
tertinggi yang ditamatkan oleh kepala rumah tangga, dalam hal ini
tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai
dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkatan terakhir suatu
jenjang di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan
tanda tamat belajar/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti
pelajaran pada kelas tertinggi tetapi sudah mengikuti ujian akhir
dan lulus, dianggap tamat sekolah.
2. Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga adalah macam Pekerjaan
yang dilakukan oleh kepala rumah tangga atau ditugaskan
33
kepadanya seminggu yang lalu. Status pekerjaan ini dikategorikan
menjadi:
? Tidak bekerja, terdiri dari kepala rumah tangga yang
seminggu yang lalu tidak atau belum bekerja.
? Pekerja di sektor formal yaitu kepala rumah tangga yang
seminggu yang lalu bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai,
berusaha di Bantu buruh tetap/buruh dibayar.
? Pekerja di sektor informal yaitu kepala rumah tangga yang
seminggu yang lalu bekerja/berusaha sendiri, berusaha
dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di
pertanian, pekerja bebas di non-pertanian, pekerja tidak
dibayar.
3. Tipe daerah adalah tipe daerah tempat tinggal responden
berdasarkan kriteria dari Badan Pusat Statistik (BPS).
4. Kartu sehat adalah bukti jaminan pembiayaan kesehatan (JPSBK)
yang dimiliki responden untuk keperluan berobat gratis.
5. Jumlah Anggota Rumah Tangga adalah banyaknya anggota rumah
tangga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang hidupnya
masih menjadi tanggungan kepala rumah tangga.
6. Jenis kelamin adalah jenis kelamin yang dimiliki seseorang baik
laki-laki maupun perempuan.
34
7. umur adalah usia seseorang pada saat pencacahan. Umur dihitung
dalam tahun dengan pembulatan kebawah atau umur pada waktu
ulang tahun yang terakhir.
8. Lama Terganggu Aktivitas adalah jumlah hari responden terganggu
kegiatan sehari-harinya dalam satu bulan terakhir karena sakit.
35
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian dan Sumber Data
Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan data sekunder
hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan
Pusat Statistik. Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan
sebelumnya maka data yang digunakan adalah data hasil Susenas yang
surveynya dilaksanakan di Kabupaten Majene tahun 2005.
B. Populasi dan Sampel
Data yang digunakan adalah data sekunder hasil Survey Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas) Kabupaten Majene tahun 2005 yang dilakukan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Susenas 2005 dilaksanakan diseluruh
Indonesia dengan ukuran sampel sebanyak 278.352 rumah tangga tersebar
baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, dengan rincian untuk sampel
Kor (tanpa modul) sebanyak 210.064 rumah tangga. Sedangkan Modul
konsumsi (Panel) sebanyak 10.640 rumah tangga.
Ukuran sampel untuk data kor Susenas 2005 Kabupaten Majene
sebanyak 608 rumah tangga dan modul konsumsi 80 rumah tangga,dengan
36
menggunakan garis kemiskinan BPS untuk Kabupaten Majene yaitu
107.309/kap/bln, yaitu jika pengeluaran perkapita penduduk/individu kurang
dari sama dengan garis kemiskinan maka penduduk tersebut masuk dalam
kriteria penduduk miskin.
Kerangka sampel yang digunakan dalam susenas 2005 terdiri dari 3
jenis yaitu, kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, kerangka sampel
untuk pemilihan kelompok segmen dalam blok sensus, dan kerangka sampel
untuk pemilihan rumah tangga dalam blok sensus/kelompok segmen terpilih
(BPS, 2005)
Pemilihan sampel untuk daerah perkotaan dan daerah pedesaan
dilakukan secara terpisah. Rancangan sampel yang digunakan untuk daerah
perkotaan adalah dua tahap. Pada tahap pertama dari kerangka sampel blok
sensus, dipilih sejumlah blok sensus secara linier systematic sampling
dengan banyaknya rumah tangga hasil listing disetiap blok sensus. Kemudian
dari setiap blok sensus terpilih, dipilih 16 rumah tangga secara linier
systematic sampling.
Rancangan sampel untuk daerah pedesaan adalah tiga tahap. Tahap
pertama dari kerangka sampel kecamatan dipilih sejumlah kecamatan secara
probability proportional to size dengan ukuran banyaknya rumah tangga
dalam kecamatan. Tahap kedua dari setiap kecamatan terpilih, dipilih
sejumlah blok sensus secara linier systematic sampling. Tahap ketiga dari
37
setiap blok sensus terpilih, dipilih 16 rumah tangga secara linier systematic
sampling (BPS,2005)
C. Spesifikasi Model
Rancangan model yang digunakan untuk melihat perilaku pengobatan
penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan adalah sebagai
berikut:
Penentuan variabel yang digunakan:
1. Variabel respon / Variabel tidak bebas (Y) yaitu perilaku pengobatan
penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan.
2. Variabel penjelas / Variabel bebas (X) yaitu
? pendidikan
? status pekerjaan
? tipe daerah
? kartu sehat
? jumlah anggota rumah tangga
? jenis kelamin
? umur
? lama terganggu kesehatan.
38
D. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dari Susenas tahun 2005 dilakukan dengan
cara wawancara langsung dengan responden yang terpilih dalam blok
sensus dengan menggunakan kuesioner VSEN05-K (Kor), dan VSEN05-M
(Modul)
E. Teknik Analisis
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2005
merupakan data sekunder. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan
analisa deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif akan dilakukan dengan
membuat tabulasi silang antara variabel-variabel yang digunakan dalam
penelitian ini yang utamanya ditujukan untuk analisis perilaku pengobatan
penduduk miskin pada pelayanan kesehatan.
Sedang analisis inferensial akan dilakukan untuk melihat faktor-faktor
yang mempengaruhi perilaku pengobatan penduduk miskin pada pelayanan
kesehatan. Mengingat variabel respon yang digunakan merupakan variabel
dikotomis, yaitu berobat atau tidak berobat pada pelayanan kesehatan, maka
akan digunakan model regresi logistik.
1. Analisis Deskriptif
Analisis data dengan menerapkan metode analisis deskriptif
dinyatakan sebagai analisis sederhana, atau yang paling sederhana. Akan
39
tetapi hasil analisis tersebut dapat menjadi masukan yang sangat berharga
untuk para pengambil keputusan dan tergantung pada bentuk analisis
tersebut. Dengan demikian, analisis deskriptif dapat merupakan analisis
penting untuk mencapai tujuan penelitian ini, terutama untuk melihat indikasi
adanya hubungan signifikan antara dua variabel sebelum dikontrol variabel
lain.
Untuk menjelaskan hubungan antara perilaku pengobatan penduduk
miskin yang mempunyai gangguan kesehatan dengan variabel sosial
demografi digunakan tabulasi silang.
Dalam analisis tabulasi silang, digunakan distribusi persentase pada
sel-sel dalam tabel sebagai dasar untuk menyimpulkan hubungan antar
variabel-variabel yang diteliti. Persentase dihitung pada variabel penjelas,
atau jumlah seratus persen adalah kategori variabel penjelas.
Hubungan variabel penjelas dengan variabel respon dilihat dengan
membandingkan distribusi persentase pada kategori-kategori variabel
penjelasnya (Singarimbun, 1989).
Analisis deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk mencermati
hubungan perilaku pengobatan penduduk miskin pada pelayanan kesehatan
dengan keadaan sosial demografi, yaitu: daerah tempat tinggal, pendidikan
kepala rumah tangga, status pekerjaan kepala rumah tangga, jenis kelamin,
umur, jumlah anggota rumah tangga, kepemilikan kartu sehat, dan lamanya
40
terganggu aktivitas. Pada analisis deskriptif ini digunakan nilai penimbang
untuk mengestimasi populasinya, sedangkan pada analisis inferensialnya
tidak menggunakan nilai penimbang.
2. Analisis Regresi Logistik
Regresi logistik merupakan salah satu model persamaan yang dipakai
dalam analisis serangkaian data-data kategorik. Metode ini merupakan
metode dasar analisis regresi data biner dalam berbagai bidang, terutama
yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Data yang dipakai terbagi
menjadi dua macam, yaitu adanya variabel respon dan variabel penjelas.
Variabel respon berskala biner (dikotomus) atau terdiri dari dua kategori
(Hosmer&Lemeshow, 1989).
Penelitian ini menggunakan variabel respon yaitu periaku pengobatan
dengan kategori berobat untuk y=1 dan tidak berobat untuk y=0, sedangkan
variabel penjelas yang digunakan yaitu variabel umur, jenis kelamin, tipe
daerah tempat tinggal, tingkat pendidikan KRT, status pekerjaan KRT, jumlah
ART, kartu sehat, dan lama terganggu aktivitas.
Analisis regresi logistik digunakan untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh variabel penjelas terhadap variabel respon. Dari model yang
terbentuk akan dilihat variabel mana saja yang; berpengaruh secara
signifikan terhadap perilaku pengobatan. Sehingga model yang terbentuk
41
akan menunjukkan peluang perilaku berobat penduduk miskin yang
mempunyai gangguan kesehatan pada pelayanan kesehatan.
Bentuk umum model regresi logistik dengan p variabel adalah sebagai
berikut:
)...exp(1
)...exp()(
110
110
pp
pp
xx
xxx
???
????
????
????
dimana )(x? adalah peluang perilaku pengobatan, dan j? adalah nilai
parameter ke-j (j=0,1,2,3,...,p). Fungsi tersebut merupakan model non linear
sehingga perlu ditransformasikan ke dalam bentuk logit agar dapat dilihat
hubungan antara variabel penjelas dengan variabel respon.
Dengan melakukan transformasi logit dari )(x? didapat persamaan yang lebih
sederhana yang merupakan fungsi linear, yaitu:
pp xxxx
xxg ????
??
???????
???
??
? ...)(1
)(ln)( 22110
Formula di atas merupakan fungsi linear dalam parameter-parameternya.
Jika dari beberapa variabel ada yang bersifat diskrit dan berskala nominal,
maka variabel tersebut tidak akan tepat jika dimasukkan dalam model. Hal ini
disebabkan angka-angka yang digunakan untuk menyatakan tingkatan
tersebut hanya sebagai identifikasi saja dan tidak mempunyai nilai numerik.
42
Dalam situasi ini diperlukan variabel dummy sebanyak k-1. misalkan variabel
ke-j yaitu xj mempunyai kj tingkatan, maka variabel dummy kj-1 dinotasikan
Dju dengan koefisien ju? , u=1, 2, 3, ..., kj-1
Maka model transformasi logit menjadi:
pp
k
ujuju xDxxxg
j
????? ?????? ??
?
1
122110 ...)(
2.1. Pengujian Parameter
2.1.1. Uji Likelihood Ratio atau Uji Signifikansi Model
Untuk mengetahui peran seluruh variabel penjelas di dalam model
secara bersama-sama dapat digunakan uji Likelihood Ratio atau uji
Signifikansi Model, dengan hipotesis:
H0: 0...21 ???? p??? (tidak ada pengaruh antara variabel penjelas
terhadap variabel respon)
H1: minimal ada satu 0?j? (minimal ada satu variabel penjelas yang
berpengaruh terhadap variabel respon)
Dengan statistik uji G= -2ln ??
???
?
kLL0
Dimana: L0 = likelihood tanpa variabel penjelas
Lk = likelihood dengan semua variabel penjelas
43
Statistik G ini mengikuti sebaran Khi-kuadrat bila n ?? dengan
derajat bebas banyaknya kategori dikurangi 1 atau (k-1) dari variabel yang
masuk dalam model. H0 ditolak jika signifikansinya kurang dari 0,05 atau nilai
G> ),(2
?? db , yang berarti dapat disimpulkan bahwa variabel penjelas x secara
keseluruhan mempengaruhi variabel respon y. H0 ditolak berarti paling sedikit
ada satu 0?j? . Untuk melihat 1? mana yang nol (tidak signifikan), dapat
digunakan uji koefisien parameter ? secara parsial (uji Wald).
2.1.2. Uji Wald
Umumnya tujuan analisis adalah untuk mencari model yang cocok
dengan keterkaitan yang kuat antara model dengan data yang ada.
Pengujian keberartian parameter (koefisien ? ) secara parsial dapat
digunakan uji Wald dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:
H0: 0?j? (tidak ada pengaruh antara variabel penjelas ke-j dengan
variabel respon)
H0: 0?j? (ada pengaruh antara variabel penjelas ke-j dengan
variabel respon)
dengan statistik ujinya yaitu:
44
2
^
^
????
?
?
????
?
?
???
???
?
j
j
SeW
?
?
dimana:
^
j? merupakan penduga j?
Se (^
j? ) adalah penduga galat baku dari j?
W diasumsikan mengikuti sebaran Khi-kuadrat bila n ?? . Tolak H0
jika W> ),1(2
?? , atau nilai dari probabilita kurang dari 0,05. H0 ditolak berarti
j? signifikan dan dapat disimpulkan bahwa variable penjelas x secara parsial
2.1.3 Odds Ratio
Odds ratio merupakan perbandingan tingkat resiko relatif dari 2 buah
nilai variabel penjelas xj atau rasio kecenderungan xj=1 terhadap xj=0. Odds
ratio dilambangkan dengan ? yang merupakan ukuran untuk mengetahui
tingkat resiko, yaitu perbandingan antara 2 nilai variabel penjelas xj, antara
kejadian-kejadian yang masuk kategori sukses dan yang gagal. Dalam
penelitian ini Odds ratio digunakan untuk mengetahui kecenderungan faktor
sosial demografi yang mempengaruhi perilaku pengobatan. Misalkan ada
variabel penjelas dengan dua kategori: satu dan nol (dengan nol digunakan
sebagai kategori referensi) maka dituliskan sebagai berikut:
45
???????
?
?
???????
?
?
??
?
??
?
?
)0(1
)0(
)1(1
)1(
^
^
^
^
^
j
j
j
j
x
x
x
x
?
?
?
?
? = exp ???
??? ^
j?
Artinya peluang atau resiko terjadinya peristiwa y=1 pada kategori xj=1
adalah sebesar exp )(^
j? kali resiko terjadinya peristiwa y=1 pada kategori
xj=0. Nilai odds ratio menunjukkan kecenderungan kategori tertentu pada
satu variabel penjelas untuk ”sukses” dibanding kategori pembanding pada
variabel yang sama. Dengan selang kepercayaan sebesar 100 (1-? )% bagi
? adalah:
exp ??
???
????
????
?
^
21
^
jj SEZ ?? ?
3 .Terapan
variabel penjelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat
pendidikan kepala rumah tangga, status pekerjaan kepala rumah tangga,
daerah tempat tinggal, jenis kelamin, umur, jumlah anggota rumah tangga,
kepemilikan kartu sehat, dan lamanya terganggu aktivitas, sedangkan
variabel responnya adalah perilaku pengobatan. Pengkategorian variabel
yang digunakan tercantum pada tabel 1.
46
Tabel 1. Pengkategorian Variabel yang Digunakan dalam Penelitian
Dummy Nama Variabel Variabel Kategori
1 2 3
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perilaku Pengobatan Y Dengan Yankes
Tanpa Yankes
1
0
Tingkat Pendidikan KRT Kategori Dasar
D1
Tidak tamat SD
Tamat SD ke atas
0
1
Jumlah ART Kategori Dasar
D2
? 5 orang
> 5 orang
0
1
Tipe Daerah Kategori dasar
D3
Perdesaan
Perkotaan
0
1
Lama Terganggu Kategori dasar
D4
? 3 hari
> 3 hari
0
1
Umur
Kategori dasar
D51
D52
D53
0-5 tahun
6-18 tahun
19-54 tahun
? 55 tahun
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
Jenis Kelamin Kategori dasar
D6
Perempuan
Laki-laki
0
1
Kartu Sehat Kategori dasar
D7
Tidak ada KS
Ada KS
0
1
Status Pekerjaan KRT
Kategori dasar
D81
D82
Tidak bekerja
Formal
Informal
0
1
0
0
0
1
47
Pengolahan data menggunakan software SPSS versi 10.0 dengan
metode backward stepwise (Wald) dan reference category adalah first,
dengan tingkat signifikan sebesar 0,05. Pada tabel Variable in the Equation
dalam output hasil pengolahan SPSS nilai Odds ratio tersebut dapat dibaca
pada kolom exp )(^
j? .
48
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Perilaku Pengobatan Penduduk Miskin yang Mengalami
Gangguan Kesehatan
Dari 49.337 penduduk miskin di Majene terdapat 7.116 (14,42 persen)
penduduk yang mengalami gangguan kesehatan atau pernah menderita
sakit, dari jumlah tersebut terdapat 56,8 persen penduduk miskin yang
pernah mengalami gangguan kesehatan melakukan pengobatan, tetapi tidak
berobat pada tempat pelayanan kesehatan, sedangkan yang melakukan
pengobatan pada pelayanan kesehatan sebesar 43,2 persen.
Tabel 2. Persentase penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan menurut perilaku pengobatan di Majene
Perilaku Pengobatan Persentase
(1) (2)
? Tidak Menggunakan Pelayanan Kesehatan (Tanpa Yankes)
? Menggunakan Pelayanan Kesehatan (Dengan Yankes)
56,8
43,2
Total 100 (7116)
Sumber: Hasil pengolahan data Susenas 2005 Kabupaten Majene
Dimana fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di Kabupaten
Majene pada tahun 2005 berupa rumah sakit umum 1 unit, puskesmas
49
sebanyak 7 unit, puskesmas pembantu sebanyak 33 unit, puskesmas keliling
sebanyak 7 unit, tempat praktek dokter umum dan spesialis sebanyak 9 unit,
bidan praktek swasta sebanyak 7 unit, dan posyandu sebanyak 175 unit.
Tingginya persentase penduduk miskin yang pernah mengalami
gangguan kesehatan tetapi melakukan pengobatan bukan di tempat
pelayanan kesehatan mengindikasikan bahwa sarana pelayanan kesehatan
yang ada di Majene belum dimanfaatkan secara optimal khususnya oleh
penduduk miskin.
B. Perilaku Pengobatan
1. Perilaku Pengobatan Berdasarkan Pendidikan KRT
Dalam penelitian yang menjadi ukuran adalah pendidikan kepala
rumah tangga seluruh penduduk miskin yang mempunyai gangguan
kesehatan, tujuan penggunaan pendidikan kepala rumah tangga sebagai
ukuran adalah karena kepala rumah tangga sebagai pemimpin dalam rumah
tangga, sehingga dia mampu membuat keputusan akan pengobatan pada
pelayanan kesehatan anggota rumah tangganya.
Pada umumnya tingkat pendidikan penduduk miskin sangat rendah,
maka variabel tingkat pendidikan dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu
kelompok pendidikan tamat SD keatas dan kelompok yang tidak tamat SD,
50
termasuk yang tidak pernah bersekolah, karena persentase penduduk miskin
yang tamat SLTP keatas sangat kecil (BPS, 2005). Dari pengolahan data
didapatkan persentase penduduk miskin yang mempunyai gangguan
kesehatan berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan perilaku
pengobatan, seperti pada tabel 3 .
Tabel 3 memperlihatkan bahwa penduduk miskin yang mempunyai
gangguan kesehatan dengan pendidikan kepala rumah tangganya tamat SD
keatas, lebih banyak yang berobat pada pelayanan kesehatan yaitu 54,6
persen, sedangkan penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan
dengan pendidikan kepala rumah tangganya tidak tamat SD, termasuk yang
tidak pernah sekolah ada 25,8 persen yang berobat pada pelayanan
kesehatan.
Tabel 3. Persentase penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan berdasarkan pendidikan KRT dan perilaku pengobatan di Majene tahun 2005
Perilaku Pengobatan
Pendidikan KRT Dengan Yankes Tanpa Yankes
Total
(1) (2) (3) (4)
Tidak tamat SD
Tamat SD keatas
25,8
54,6
74,2
45,4
100 (2812)
100 (4304)
Total 43,2 (3077) 56,8 (4039) 100 (7116)
Sumber: Hasil Pengolahan data Susenas 2005 Kabupaten Majene
51
Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan pemanfaatan fasilitas
pengobatan semakin meningkat. Hasil ini sesuai dengan beberapa penelitian
yang sudah dilakukan sebelumnya, diantaranya yang dilakukan oleh
Notoatmodjo dan Supriyadi.
Notoatmodjo, dkk (Yulianingsih, 2001) menyatakan tingkat pendidikan
yang lebih tinggi akan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang canggih.
Tingkat pendidikan mempengaruhi kesadaran akan pentingnya arti
kesehatan bagi diri dan lingkungan yang dapat mendorong kebutuhan akan
pelayanan kesehatan.
Penelitian Supriyadi (2004) menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat
pendidikan maka cenderung semakin tinggi penggunaan pelayanan
kesehatan formal, dan semakin rendah penggunaan pelayanan kesehatan
informal.
2. Perilaku Pengobatan Berdasarkan Tipe Daerah Tempat Tinggal
Karakteristik wilayah berhubungan dengan pengobatan pada
pelayanan kesehatan, di negara-negara berkembang sebagian besar
penduduknya tinggal di daerah pedesaan yang kekurangan sarana
kesehatan modern, individu yang tinggal di daerah perkotaan memiliki
probabilitas untuk akses lebih tinggi dibandingkan individu yang tinggal di
daerah pedesaan, daerah perkotaan memiliki infrastruktur lebih baik
52
dibandingkan individu yang tinggal di daerah pedesaan, sehingga akses di
daerah perkotaan lebih mudah.
Pada tabel 4 memperlihatkan bahwa dari 2.332 penduduk miskin yang
mempunyai gangguan kesehatan dan tinggal di daerah perkotaan, ada 43,2
persen penduduk yang berobat pada pelayanan kesehatan. Sedangkan dari
4784 penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan dan tinggal di
daerah pedesaan, terdapat 43,3 persen penduduk berobat pada pelayanan
kesehatan.
Tabel 4. Persentase penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan berdasarkan tipe daerah dan perilaku pengobatan di Majene tahun 2005
Perilaku Pengobatan Tipe Daerah
Dengan Yankes Tanpa Yankes Total
(1) (2) (3) (4)
Perkotaan
Pedesaan
43,2
43,3
56,8
56,7
100 (2332)
100 (4784)
Total 43,2 (3077) 56,8 (4039) 100 (7116)
Sumber: Hasil Pengolahan data Susenas 2005 Kabupaten Majene
Dari data di atas terlihat bahwa persentase penduduk yang berobat
baik yang tinggal di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan tidak
berbeda jauh atau relatif sama yaitu masing-masing 43,3 persen dan 43,2
persen hal ini dikarenakan keadaan geografis antara daerah perkotaan dan
53
perkotaan di Kabupaten Majene hampir sama, dan pembangunan fasilitas
kesehatan relative sudah merata sampai di daerah pedesaan. Menurut Azwar
(1985) penyebaran masalah kesehatan dapat disebabkan oleh hal-hal
khusus diantaranya keadaan geografis misalnya letak wilayah.
3. Perilaku Pengobatan Berdasarkan Lama Terganggu
Lamanya menderita sakit (disability day) berhubungan langsung
terhadap perasaan akan seriusnya penyakit yang dirasakan. Dari pengolahan
data didapatkan persentase penduduk miskin yang mempunyai gangguan
kesehatan berdasarkan lama terganggu dan perilaku pengobatan, seperti
pada tabel 5 di bawah ini:
Tabel 5. Persentase penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan berdasarkan lama terganggu dan perilaku pengobatan di Majene tahun 2005
Perilaku Pengobatan Lama
Terganggu Dengan Yankes Tanpa Yankes Total
(1) (2) (3) (4)
= 3 Hari
> 3 Hari
24,3
66,2
75,7
33,8
100 (3901)
100 (3215)
Total 43,2 (3077) 56,8 (4039) 100 (7116)
Sumber: Hasil Pengolahan data Susenas 2005 Kabupaten Majene
Tabel 5 memperlihatkan bahwa penduduk miskin yang mempunyai
gangguan kesehatan lebih dari tiga hari lebih cenderung berobat pada
54
pelayanan kesehatan yaitu 66,2 persen, sedangkan persentase penduduk
miskin yang mempunyai gangguan kesehatan kurang dari atau sama dengan
tiga hari untuk berobat pada pelayanan kesehatan yaitu 24,3 persen,
sehingga kebanyakan tidak menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan.
Hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Phelp dan penelitian
yang dilakukan oleh Supriyadi.
Phelp (Yulianingsih, 2001) mengemukakan bahwa jumlah hari sakit
berhubungan positif dengan angka kunjungan ke dokter.
Penelitian Supriyadi (2004) menyebutkan semakin lama hari
terganggu maka pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan cenderung
semakin menigkat. Musaddad et al (1982) menyatakan bahwa faktor-faktor
jarak ke fasilitas kesehatan, pendidikan ibu, keterpaparan terhadap media
massa, dan lama terganggu berperanan penting dalam pengaruhnya
terhadap pencarian pelayanan kesehatan.
4. Perilaku Pengobatan Berdasarkan Kepemilikan Kartu Sehat
Kartu sehat adalah bukti diri yang diberikan kepada rumah tangga
miskin yang termasuk dalam sasaran program JPSBK, untuk mendapatkan
jaminan pelayanan kesehatan gratis. Kartu sehat hanya diberikan satu buah
kepada setiap rumah tangga miskin untuk digunakan oleh seluruh anggota
55
rumah tangganya, kartu sehat dikelompokkan menjadi ada dan tidaknya kartu
sehat.
Tabel 6 memperlihatkan bahwa persentase penduduk miskin yang
mempunyai gangguan kesehatan dan tersedia kartu sehat hanya sebesar
32,4 persen yang berobat pada pelayanan kesehatan. Sedangkan penduduk
miskin yang mempunyai gangguan kesehatan dan tidak tersedia kartu sehat
ada 50,2 persen yang berobat pada pelayanan kesehatan.
Tabel 6. Persentase penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan berdasarkan kartu sehat dan perilaku pengobatan di Majene tahun 2005
Perilaku Pengobatan Kartu Sehat
Dengan Yankes Tanpa Yankes Total
(1) (2) (3) (4)
Ada KS
Tidak Ada KS
32,4
50,2
67,6
49,8
100 (2784)
100 (4332)
Total 43,2 (3077) 56,8 (4039) 100 (7116)
Sumber: Hasil Pengolahan data Susenas 2005 Kabupaten Majene
Persentase penduduk miskin yang tersedia kartu sehat lebih kecil
dibandingkan penduduk miskin yang tidak tersedia kartu sehat untuk berobat
pada pelayanan kesehatan, kartu sehat yang merupakan bukti pembayaran
gratis tidak membuat akses pemegangnya meningkat terhadap pelayanan
kesehatan. Menurut WHO dalam Yulianingsih (2001), ini dikarenakan untuk
56
mendapatkan pelayanan kesehatan diperlukan tidak hanya sekedar biaya
untuk kesehatan sendiri, tetapi ada biaya lainnya. Biaya tersebut adalah
biaya transportasi, biaya untuk obat, atau biaya untuk hilangnya waktu kerja.
5. Perilaku Pengobatan Berdasarkan Kelompok Umur.
Menurut Anderson (Herlina, 2001) umur adalah komponen predisposisi
keluarga dalam penggunaan pelayanan kesehatan, berarti pola pemanfaatan
pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh individu-individu dari berbagai
kelompok usia. Untuk memudahkan analisis maka umur dikelompokkan
menjadi empat yaitu umur 0-5 tahun, 6-18 tahun, 19-54 tahun dan = 55 tahun.
Dari data didapatkan persentase penduduk miskin yang mempunyai
gangguan kesehatan berdasarkan kelompok umur dan perilaku kesehatan,
tabel 7 memperlihatkan bahwa penduduk miskin yang berumur = 55 tahun
dengan gangguan kesehatan mempunyai persentase untuk berobat pada
pelayanan kesehatan paling banyak yaitu sebesar 55,5 persen, kemudian
disusul oleh yang berumur 0-5 tahun ada sebanyak 46,1 persen dan
kelompok umur 19-54 tahun yaitu sebesar 44,3 persen untuk pergi ke fasilitas
kesehatan.
Kelompok umur yang paling sedikit tidak berobat pada pelayanan
kesehatan adalah umur 6-18 tahun yaitu sebanyak 27,2 persen. Penelitian
Supriyadi (2004) menyebutkan adanya hubungan yang bermakna antara
57
umur dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan bahwa semakin
bertambahnya umur maka cenderung semakin tinggi pemanfaatan pelayanan
kesehatan rawat jalan.
Tabel 7. Persentase penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan berdasarkan kelompok umur dan perilaku pengobatan di Majene tahun 2005
Perilaku Pengobatan Umur
Dengan Yankes Tanpa Yankes Total
(1) (2) (3) (4)
0-5 tahun
6-18 tahun
19-54 tahun
= 55 tahun
46,1
27,2
44,3
55,5
53,9
72,8
55,7
44,5
100 (990)
100 (1602)
100 (2911)
100 (1613)
Total 43,2 (3077) 56,8 (4039) 100 (7116)
Sumber: Hasil Pengolahan data Susenas 2005 Kabupaten Majene
Namun berdasarkan data di atas untuk kabupaten Majene pada tahun
2005 terdapat sedikit perbedaan dimana untuk penduduk miskin yang
berumur 0-5 tahun ternyata lebih banyak berobat ke fasilitas kesehatan
dibandingkan kelompok umur 19-54 tahun. Menurut penulis hal ini
disebabkan pada usia balita yaitu 0-5 tahun adalah usia yang rentan
terhadap penyakit karena daya tahan tubuh yang masih kurang, hal ini sesuai
58
dengan teori yang dikemukakan oleh Azwar dalam bukunya 1 yang
menyatakan umur merupakan variabel penting dalam mempelajari suatu
masalah kesehatan karena umur terkait dengan daya tahan tubuh, pada
umumnya daya tahan tubuh orang dewasa jauh lebih kuat daripada daya
tahan tubuh balita.
Fenomena diatas jg terkait dengan data yang menunjukkan bahwa
tingkat pendidikan penduduk miskin di Kabupaten Majene pada tahun 2005
masih rendah sehingga masih banyak orang tua yang kurang mengerti
bagaimana memperlakukan anaknya dengan baik, menjaga agar tidak
mudah terinfeksi oleh kuman. Seperti yang disebutkan oleh Thabrany
(1995), bahwa secara teoritis pendidikan meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran tentang penyakit dan pencegahan penyakit.
6. Perilaku Pengobatan Berdasarkan Jumlah ART
Dari pengolahan data didapatkan persentase penduduk miskin yang
mempunyai gangguan kesehatan berdasarkan jumlah anggota rumah tangga
dan perilaku pengobatan. Pada Tabel 8 memperlihatkan bahwa dari 2.136
penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan dan tinggal bersama
keluarga kecil (ART < 5 orang) ada 23,5 persen penduduk yang berobat pada
pelayanan kesehatan. Sedangkan dari 4.980 penduduk miskin yang 1 Program Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan (Aplikasi Prinsip Pemecahan Masalah). Jakarta
59
mempunyai gangguan kesehatan dan tinggal bersama keluarga besar (ART =
5 orang) terdapat 51,7 persen penduduk berobat pada pelayanan kesehatan.
Tabel 8. Persentase penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan berdasarkan jumlah ART dan perilaku pengobatan di Majene tahun 2005
Perilaku Pengobatan Jumlah Anggota
Rumah Tangga
Miskin Dengan Yankes Tanpa Yankes
Total
(1) (2) (3) (4)
< 5 Orang
= 5 Orang
23,5
51,7
76,5
48,3
100 (2136)
100 (4980)
Total 43,2 (3077) 56,8 (4039) 100 (7116)
Sumber: Hasil Pengolahan data Susenas 2005 Kabupaten Majene
Hasil ini sesuai dengan penelitian Yulianingsih (2001) yang
menyebutkan bahwa orang yang berada pada keluarga besar memiliki akses
yang lebih tinggi daripada orang yang berada pada keluarga kecil.
7. Perilaku Pengobatan Berdasarkan Status Pekerjaan KRT
Variabel status pekerjaan dalam penelitian ini yang menjadi ukuran
adalah status pekerjaan kepala rumah tangga, karena apabila pengukuran
status pekerjaan dilakukan pada semua responden akan menimbulkan bias
pengukuran disebabkan banyaknya anggota rumah tangga yang tidak
60
bekerja (anak-anak, usia sekolah). Status pekerjaan kepala rumah tangga
penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan terbagi dalam tiga
kategori yaitu tidak bekerja, pekerja di sektor formal dan pekerja di sektor
informal.
Tabel 9 memperlihatkan bahwa dari 1192 penduduk miskin yang
mempunyai gangguan kesehatan dengan kepala rumah tangganya bekerja di
sektor formal, ada 63,5 persen penduduk berobat pada pelayanan
kesehatan, hanya 45,9 persen penduduk miskin yang mempunyai gangguan
kesehatan dengan kepala rumah tangganya tidak bekerja/pengangguran
berobat pada pelayanan kesehatan.
Tabel 9. Persentase penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan berdasarkan status pekerjaan KRT dan perilaku pengobatan di Majene tahun 2005
Perilaku Pengobatan
Status Pekerjaan
KRT Dengan Yankes Tanpa Yankes Total
(1) (2) (3) (4)
Tidak Bekerja
Formal
Informal
45,9
63,5
38,1
54,1
36,5
61,9
100 (831)
100 (1192)
100 (5093)
Total 43,2 (3077) 56,8 (4039) 100 (7116)
Sumber: Hasil Pengolahan data Susenas 2005 Kabupaten Majene
61
Sedangkan dari 5093 penduduk miskin yang mempunyai gangguan
kesehatan dengan kepala rumah tangganya bekerja di sektor informal,
terdapat 38,1 persen penduduk yang berobat pada pelayanan kesehatan.
Hasil di atas sesuai dengan penelitian Supriyadi (2004) yang menyebutkan
ada hubungan positif antara pekerjaan kepala keluarga dengan pemanfaatan
pelayanan kesehatan.
8. Perilaku Pengobatan Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis kelamin tercatat sebagai laki-laki dan perempuan, tabel 10
memperlihatkan bahwa penduduk miskin perempuan yang mempunyai
gangguan kesehatan 47,1 persen berobat pada pelayanan kesehatan,
sedangkan 48,5 persen untuk laki-laki. Hal ini memperlihatkan bahwa laki-laki
dan perempuan memiliki persentase yang relatif sama untuk berobat pada
pelayanan kesehatan.
Tabel 10. Persentase penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan berdasarkan jenis kelamin dan perilaku pengobatan di Majene tahun 2005
Perilaku Pengobatan Jenis Kelamin
Dengan Yankes Tanpa Yankes Total
(1) (2) (3) (4)
Laki-laki
Perempuan
48,5
47,1
51,5
52,9
100 (3194)
100 (3922)
Total 43,2 (3077) 56,8 (4039) 100 (7116)
Sumber: Hasil Pengolahan data Susenas 2005 Kabupaten Majene
62
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuliawati (2002) yang
dalam penelitiannya menemukan bahwa tidak ada perbedaan laki-laki dan
perempuan dalam berobat pada pelayanan kesehatan.
Pada penelitian ini jenis kelamin bukan merupakan faktor yang
berhubungan dengan perilaku pengobatan pada pelayanan kesehatan,
dimana menurut asumsi peneliti dikarenakan bahwa keluhan kesehatan yang
terdapat pada data Susenas 2005 dapat menyerang siapa saja dan tidak
membedakan gender. Hal ini didukung oleh komposisi penduduk miskin yang
mempunyai gangguan kesehatan berdasarkan jenis kelamin adalah hampir
sama yaitu 45 persen laki-laki dan 55 persen perempuan.
C. Pengaruh Variabel Sosial Demografi terhadap Perilaku
Pengobatan Pada Pelayanan Kesehatan
Pembahasan ini menggunakan analisis regresi logistik, untuk
keperluan analisis lebih lanjut antara faktor sosial demografi dengan perilaku
pengobatan penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan di
Majene tahun 2005.
Taraf nyata yang digunakan dalam uji signifikansi model, jika tingkat
signifikansi dalam model tersebut lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka
model tersebut sudah tepat yang berarti paling sedikit terdapat satu variabel
yang signifikan mempengaruhi model. Penjelasan besar hubungan antara
63
masing-masing variabel penjelas yang memiliki pengaruh terhadap perilaku
pengobatan penduduk miskin, digunakan nilai Odd ratio.
Penghitungan regresi logistik dilakukan dengan menggunakan paket
program SPSS for windows version 10,0 dengan metode Backward Stepwise
(Wald) untuk memilih model regresi logistik yang terbaik dan reference
category adalah first, dengan analisa output sebagai berikut:
a. Uji Signifikansi Model
Uji Signifikansi model digunakan untuk menentukan model regresi
logistik yang menggunakan delapan variabel penjelas yang berpengaruh
terhadap perilaku pengobatan penduduk miskin. Hal ini dapat dilakukan
dengan membandingkan p-value dengan taraf nyata yang telah ditentukan
sebesar 0,05.
Berdasarkan nilai signifikansi = 0,000 < 0,05 maka keputusan H0
ditolak, hal ini mengindikasikan bahwa minimal ada satu variabel dari delapan
variabel penjelas yang berpengaruh terhadap perilaku pengobatan penduduk
miskin yang mempunyai gangguan kesehatan pada pelayanan kesehatan.
b. Uji Parameter Model
Model regresi logistik yang dipakai adalah bertahap (backward). Uji
parameter model dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel
penjelas secara parsial terhadap variabel responnya. Berdasarkan uji
keberartian secara parsial dengan menggunakan statistik Wald dimana nilai
64
ini merupakan hasil kuadrat dari pembagian antara estimasi koefisien ß
terhadap estimasi standar error koefisien ß yang dihasilkan pada output
analisis.
Berdasarkan output regresi logistik, diperoleh nilai penduga parameter,
statistik uji wlad, dan nilai signifikansi variabel-variabel yang masuk dalam
model regresi logistik dan berpengaruh terhadap perilaku pengobatan
penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan pada pelayanan
kesehatan.
Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat bahwa ada tiga variabel yang
mempunyai pengaruh secara nyata terhadap perilaku pengobatan penduduk
miskin yang mempunyai gangguan kesehatan, yaitu variabel pendidikan
kepala rumah tangga (KRT), jumlah anggota rumah tangga (ART) dan lama
terganggu karena masing-masing variabel memiliki statistik uji Wald > ?2(1:0,05)
= 3,841 atau nilai signifikansi kurang dari (<) a = 0,05.
Sedangkan variabel yang tidak mempunyai pengaruh secara nyata
terhadap perilaku pengobatan penduduk miskin yang mempunyai gangguan
kesehatan pada pelayanan kesehatan adalah umur, status pekerjaan kepala
rumah tangga, jenis kelamin, kartu sehat, dan tipe daerah karena memiliki
statistik uji Wald kurang dari (<) ?2(1:0,05) = 3,841 atau nilai signifikansi lebih
besar (>) dari a = 0,05.
65
Tabel 11. Nilai penduga parameter, statistik Uji Wald, dan nilai signifikansi
Variabel ?̂ Se( ?̂ ) Wald df Sig
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pendidikan KRT 1,551 0,45 11,897 1 0,001
Jumlah ART 1,198 0,475 6,369 1 0,012
Tipe Daerah -0,115 0,500 0,053 1 0,818
Lama Terganggu 2,146 0,432 24,705 1 0,000
Umur (0-5 th) 6,068 3 0,108
Umur (6-18 th) -1,064 0,729 2,130 1 0,144
Umur (19-54 th) 0,125 0,654 0,037 1 0,848
Umur (= 55 th) 0,330 0,722 0,209 1 0,648
Jenis Kelamin -0,244 0,426 0,328 1 0,567
Kartu Sehat -0,425 0,461 0,841 1 0,357
STAT_KRT (Tidak Bekerja) 0,382 2 0,826
STAT_KRT (Formal) -0,542 0,880 0,379 1 0,538
STAT_KRT (Informal) -0,396 0,768 0,265 1 0,607
Sumber: Hasil pengolahan data Susenas 2005 Kabupaten Majene
Berdasarkan pengujian parameter model yang telah dilakukan maka
diperoleh model peluang regresi logistik berdasarkan variabel yang masuk
dalam model, adalah:
66
? ???̂ = ? ?
? ?421
421
146,2198,1551,1146,31146,2198,1551,1146,3
DDDExpDDDExp
?????????
? ? 421 146,2198,1551,1146,3ˆ DDDxg ?????
Keterangan: D1 = Tingkat Pendidikan KRT
D2 = Jumlah ART
D4 = Lama Terganggu
Sebagai contoh penduduk miskin yang mempunyai gangguan
kesehatan lebih dari tiga hari, tinggal bersama keluarga kecil (ART<5 orang)
dan kepala rumah tangganya tamat SD ke atas, maka model persamaan
regresi logistik di atas didapat besarnya peluang untuk berobat pada
pelayanan kesehatan sebagai berikut:
? ???̂ = ? ?
? ?)1(146,2)0(198,1)1(551,1146,31)1(146,2)0(198,1)1(551,1146,3
?????????
ExpExp
=? ?
? ?551,01551,0
ExpExp?
= 0,6344
Jadi peluang penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan
untuk berobat pada pelayanan kesehatan yang memiki gangguan kesehatan
lebih dari tiga hari, tinggal bersama keluarga kecil (ART<5 orang) dan kepala
rumah tangganya tamat SD keatas adalah 0,6344 (63,44 persen).
67
Berdasarkan koefisien regresi ?̂ pada model peluang regresi logistik
dapat dilihat hubungan antara variabel penjelas yang berpengaruh terhadap
perilaku pengobatan penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan
pada pelayanan kesehatan dengan menganggap faktor lain konstan, seperti
berikut:
1. Terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan kepala rumah
tangga dengan perilaku pengobatan. Hal ini berarti bahwa penduduk
miskin yang mempunyai gangguan kesehatan dengan kepala rumah
tangga tamat SD keatas lebih berobat pada pelayanan kesehatan dari
penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan dengan
kepala rumah tangga tidak tamat SD, termasuk yang tidak pernah
bersekolah.
2. Terdapat hubungan positif antara jumlah anggota rumah tangga
dengan perilaku pengobatan. Hal ini berarti bahwa penduduk miskin
yang mempunyai gangguan kesehatan dan tinggal bersama keluarga
besar (ART=5 orang) lebih berobat pada pelayanan kesehatan dari
penduduk miskin yang mempunyai gangguan kesehatan dan tinggal
bersama keluarga kecil (ART<5 orang).
3. Terdapat hubungan positif antara lama terganggu dengan perilaku
pengobatan. Hal ini berarti bahwa penduduk miskin yang mempunyai
gangguan kesehatan lebih dari tiga hari, lebih berobat pada
68
pelayanan kesehatan dari penduduk miskin yang mempunyai
gangguan kesehatan kurang dari atau sama dengan tiga hari.
Klasifikasi model digunakan untuk menentukan tingkat ketepatan
model dalam memprediksi. Dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan
tingkat ketepatan model dalam memprediksi perilaku pengobatan penduduk
miskin yang mempunyai gangguan kesehatan pada pelayanan kesehatan,
tingkat ketepatan model dalam memprediksi perilaku pengobatan penduduk
miskin yang mempunyai gangguan kesehatan pada pelayanan kesehatan
sebesar 71,6 persen.
C. Odd Ratio
Menurut Hosmer dan Lemeshow (1989), penarikan kesimpulan dari
model regresi logistik yang tepat adalah dengan menganalisis nilai Odd ratio
dari variabel dalam model.
Nilai ini diperoleh dengan mengeksponensialkan koefisien dari variabel
dalam model regresi logistik yang terbentuk. Dalam penelitian ini akan
digunakan rujukan (reference category) first untuk menganalisis Odd ratio,
seperti pada tabel 12.
Berdasarkan tabel 12 dapat dilihat nilai odd ratio atau rasio
kecenderungan berobat pada pelayanan kesehatan, sebagai berikut:
69
1. Pendidikan KRT
Nilai odd ratio untuk pendidikan kepala rumah tangga adalah 4,714, ini
berarti bahwa kecenderungan penduduk miskin dengan gangguan kesehatan
yang kepala rumah tangganya tamat SD keatas untuk berobat pada
pelayanan kesehatan 4,714 kali dibandingkan penduduk miskin dengan
gangguan kesehatan yang kepala rumah tangganya tidak tamat SD,
termasuk yang tidak pernah bersekolah.
Jadi dapatlah dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan
maka cenderung semakin berobat pada pelayanan kesehatan. Hasil ini
sesuai dengan penelitian Supriyadi (2004), bahwa semakin tinggi tingkat
pendidikan kepala rumah tangga maka cenderung semakin tinggi
penggunaan pelayanan kesehatan formal, dan semakin rendah penggunaan
pelayanan kesehatan informal.
Tingginya penggunaan pelayanan kesehatan pada kelompok yang
berpendidikan kemungkinan disebabkan oleh utuhnya pemahaman tentang
pola hidup sehat dengan upaya preventif yang efektif dan efisien.
Pencegahan dini, pemulihan dan pembatasan kecacatan menjadi suatu hal
yang mendorong mereka menggunakan pelayanan kesehatan tersebut.
Feldstein (1993) seperti dikutip Supriyadi menyatakan bahwa
pendidikan dapat mempengaruhi demand (permintaan) untuk pelayanan
medis. Tingkat pendidikan kepala keluarga akan sangat menentukan
70
pencarian pengobatan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan manakala
anggota keluarga mengalami gangguan sakit.
Tabel 12. Nilai penduga parameter dan Odd Ratio
Variabel ?̂ Exp ( ?̂ )
(1) (2) (3)
Jumlah ART 1,198 3,315
Lama Terganggu 2,146 8,552
Pendidikan KRT 1,551 4,714
Sumber: Hasil pengolahan data Susenas 2005 Kabupaten Majene
Thabrany (1995) menyampaikan bahwa secara teoritis pendidikan
dapat mempengaruhi status kesehatan seseorang dengan dua cara.
Pertama, pendidikan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang
penyakit dan pencegahan penyakit. Kedua, pengaruh pendidikan pada status
kesehatan melalui pendapatan/income. Secara umum orang yang
berpendidikan baik memiliki lebih besar kesempatan mendapatkan
penghasilan, sehingga mereka akan mendapatkan nutrisi yang lebih baik,
lingkungan yang sehat dan perawatan kesehatan yang terjaga. Green
(Supriyadi, 2004) mengkategorikan pengetahuan sebagai faktor predisposisi
dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu tidak berlebihan
bila upaya merubah perilaku pengobatan penduduk miskin pada pelayanan
71
kesehatan perlu adanya intervensi terus menerus terhadap bidang
pendidikan.
2. Jumlah Anggota Rumah Tangga (JART)
Nilai odd ratio untuk jumlah anggota rumah tangga adalah 3,315, ini
berarti bahwa kecenderungan penduduk miskin dengan gangguan kesehatan
dan tinggal bersama keluarga besar (ART=5 orang) untuk berobat pada
pelayanan kesehatan 3,315 kali dibandingkan penduduk miskin dengan
gangguan kesehatan dan tinggal bersama keluarga kecil (ART<5 orang).
Hasil ini sejalan dengan penelitian Yulianingsih (2001) yang
menyatakan bahwa penduduk yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih
dari empat orang ternyata akan memanfaatkan pelayanan kesehatan 1,07
kali dibandingkan dengan penduduk yang jumlah anggota keluarganya
kurang dari atau sama dengan empat orang.
Penulis mengasumsikan bahwa banyaknya anggota rumah tangga
akan meningkatkan pendapatan/income rumah tangga tersebut karena ada
banyak anggota rumah tangga yang bekerja. Feldstein (Yuliawati, 2002)
menyatakan bahwa kenaikan 10 persen penghasilan menaikkan 15 persen
penggunaan pelayanan kesehatan. Anderson (Supriyadi, 2004) menyatakan
bahwa besarnya anggota keluarga dan terdapatnya anggota keluarga yang
72
masih balita, sudah dewasa atau telah menikah cenderung lebih sering
menggunakan pelayanan kesehatan.
3. Lama terganggu
Nilai odd ratio untuk lama terganggu adalah 8,552, ini berarti bahwa
kecenderungan penduduk miskin dengan gangguan kesehatan lebih dari tiga
hari untuk berobat pada pelayanan kesehatan 8,552 kali dibandingkan
dengan penduduk miskin dengan gangguan kesehatan kurang dari atau
sama dengan tiga hari.
Dari hasil tersebut memberikan bukti bahwa tingkat kesehatan untuk
memeriksakan atau berkunjung ke pelayanan kesehatan semakin tinggi
seiring semakin lamanya hari terganggu. Kebutuhan akan pelayanan
kesehatan (need for health service) adalah jumlah dan jenis pelayanan
kesehatan yang diperlukan untuk mengurangi atau meringankan masalah
kesehatan.
Supriyadi (2004) dalam penelitiannya tentang pemanfaatan pelayanan
kesehatan rawat jalan di Banyumas menyebutkan bahwa semakin lama hari
terganggu karena sakit maka pemanfaatan pelayanan kesehatan semakin
meningkat.
73
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku pengobatan penduduk miskin yang
mempunyai gangguan kesehatan di Kabupaten Majene sebagai berikut:
1. Secara signifikan dipengaruhi oleh tiga variabel dengan R2 = 38,8 %
yaitu :
- Pendidikan kepala rumah tangga
- Jumlah anggota rumah tangga.
- Lamanya terganggu aktivitas.
2. Tidak signifikan adal lima variabel dengan R2 = 5,1 % yaitu :
- Status pekerjaan kepala rumah tangga
- Tipe daerah
- Kepemilikan kartu sehat
- Jenis kelamin
- umur.
3. Penduduk miskin di Kabupaten Majene memiliki tingkat pendidikan
yang rendah terutama pada kepala rumah tangganya, hal ini
74
mempengaruhi cara pandang mereka tentang pentingnya kesehatan.
Adanya kecenderungan penduduk miskin baru berobat setelah
mengalami gangguan kesehatan lebih dari tiga hari, jumlah anggota
rumah tangga miskin masih didominasi rumah tangga dengan
anggota rumah tangga lebih dari lima orang.
B. Saran
Dengan melihat hasil pembahasan dan kesimpulan ada beberapa
saran yang akan disampaikan :
1. Diperlukan kebijakan pembangunan pada program pembangunan
bidang kesehatan dan program pendukungnya di Kabupaten Majene;
seperti Program Lingkungan Sehat, dengan mewujudkan mutu
lingkungan hidup yang lebih sehat agar masyarakat terbebas dari
masalah kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak
sehat. Peningkatan program KB dalam upaya pengendalian kelahiran,
serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, karena KB
dapat mengubah struktur kependudukan, tidak saja dalam arti
menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk namun
juga mengubah pandangan hidup penduduk terhadap nilai anak serta
kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Penambahan Kartu Sehat
untuk membantu penduduk miskin dalam menjalani pengobatan, lebih
75
dari 4.000 penduduk miskin belum memiliki Kartu Sehat dari 7.116
penduduk miskin yang ada di Kabupaten Majene
2. Penduduk dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban
dalam pembangunan, oleh karena dalam proses membangun,
masyarakat juga perlu meningkatkan kualitas kesehatannya secara
aktif dalam berbagai kesempatan.
3. Penelitian ini dirasakan masih belum komprehensif, sehingga perlu
dikembangkan dengan melihat faktor lain yang mempengaruhi
perilaku pengobatan penduduk miskin, seperti kepuasan pelayanan,
kepercayaan, nilai-nilai budaya, jarak ke sarana kesehatan, sikap dan
perilaku petugas kesehatan, tipe dan frekuensi penyakit, serta
keterpaparan terhadap media massa, demikian juga dengan
keterbatasan metodologi penelitian yang digunakan, masih perlu
diujicoba dengan menggunakan metodologi yang berbeda pada
penelitian berikutnya.
76
DAFTAR PUSTAKA
Agresti A. 1990. Categorical Data Analysis. Canada:JohnWiley & Sons.Inc. Agung IGN . 2000. Analisis data kategorik. Tidak di publikasikan. Andrayanti SL. 1999. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan
Kartu Sehat di Kalangan Keluarga Miskin di Kabupaten Limo Puloh Kota dan Pesisir Selatan Propinsi Sumatra Barat Tahun 1999 [Tesis]. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
Azwar A.1993. Program Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan (Aplikasi
Prinsip Pemecahan Masalah). Jakarta: Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia.
Badan Pusat Statistik [BPS]. 2005a . Statistik Kesejahteraan Rakyat 2005.
Jakarta: BPS . 2005b . Data dan Informasi Kemiskinan 2005.
Jakarta: BPS . 2005c. Majene Dalam Angka 2005 . Jakarta:
BPS . 2005d . Pedoman Pencacah Kor dan Modul
Susenas 2005 . Jakarta : BPS . 2005e . Statistik Indonesia Tahun 2004. Jakarta:
BPS.
77
Budiantini S. 2003. Analisis Rumah Tangga Miskin yang Dikepalai oleh Wanita di Propinsi Gorontalo Tahun 2002 [Skripsi]. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
Budiarti W. 2004. Analisis Karakteristik Demografi, Sosial dan Ekonomi
Penduduk Miskin di DKI Jakarta Tahun 2002 [Skripsi] . Jakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik .
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan [Depdikbud]. 1996. Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Jakarta: Depdikbud RI.
Departemen Kesehatan RI [Depkes RI]. 1992. Undang-Undang Republik
Indonesia Tahun 1992 tentang Kesehatan. Jakarta: Depkes RI . . 1999a. Visi, Misi, Kebijakan dan
Strategi Pembangunan Kesehatan. Indonesia Sehat 2010. Jakarta: Depkes RI.
. 1999b . Pedoman Pelaksanaan
Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK). Jakarta: Depkes RI.
Herlina M . 2001. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Jenis
Pengobatan Alternatif pada Masyarakat Pengguna Pengobatan Alternatif di Kota Bengkulu Tahun 2001 [Tesis]. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
Hosmer DW , Lemeshow S. 1989. Appilied Logistic Regression. Canada:
John Wilei & Sons.Inc Mubarok I. 2005. Analisis Perilaku Pengobatan Penduduk Jawa Barat tahun
2004 [Skripsi]. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
78
Nacrhowi ND, Usman H. 2002. Penggunaan Teknik Ekonometri: pendekatan populer dan Praktis Dilengkapi Tehnik Analisis & Pengolahan Data dengan Menggunakan Paket Program SPSS. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Nandipita. 2000. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku
Pencarian Pengobatan pada Pria/Klien yang Menderita Penyakit Menular Seksual yang Berkunjung ke Lokalisasi/Tempat Prostitusi di Kabupaten Indramayu Tahun 2000 [Tesis] Jakarta: Fakultas Kesehatan masyarakat, Universitas Indonesia.
Purnamasari D. 2004. Analisis Menejemen Pelaksanaan Program Pelayanan
Kesehatan Keluarga miskin di Puskesmas Kota Depok Tahun 2004[Skripsi]. Jakarta:Fakultas Kesehatan masyarakat, Universitas Indonesia.
Purwatmoko SB. 2004. Pengaruh Tingkat Ekonomi Keluarga terhadap
Pencarian Pengobatan bagi Balita ISPA di Indonesia tahun 2001[Tesis]. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
Pusponegoro NH. 2003. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Alat
Kontrasepsi Suntikan atau IUD di Kecamatan Jenawi dan Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar tahun 2002 [skripsi]. Jakarta: Sekolah tinggi ilmu Statistik.
Santoso S. 2004. SPSS Versi 10.0 Mengolah Data Statistik Secara
Profesional. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Siegel S. 1994. Statistik Non Parametrik untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta:
Pustaka Utama.
79
Supriyadi. 2004. Analisis Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan di Kabupaten Banyumas tahun 2001 [skripsi]. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
Thabrany H, et.al.1998. Analisa Data Susenas Tentang Pemanfaatan
Pelayanan Kesehatan Peserta Wajib PT. Askes [Laporan penelitian]. Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
Usman H. 2002. Determinan dan Eksploitasi Pekerja Anak-Anak di Indonesia
(Analisis Data Sunsenas 2000 Kor) [Tesis]. Jakarta: Program Kajian Kependudukan dan Ekonomi Sumber Daya Manusia, Universitas Indonesia.
Yulianingsih. 2001. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan
Pelayanan Kesehatan pada Keluarga miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 1999 [Skrispi]. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
Yuliawati. 2002. Faktor-Faktor Sosial Demografi yang Berhubungan dengan
Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Banten Tahun 2001 [Skripsi]. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
80
LAMPIRAN 1 : Output Logistic Regression
Case Processing Summary
148 100.00 .0
148 100.00 .0
148 100.0
Unweighted Casesa
Included in AnalysisMissing CasesTotal
Selected Cases
Unselected CasesTotal
N Percent
If weight is in effect, see classification table for the totalnumber of cases.
a.
Dependent Variable Encoding
0
1
Original Valuetidak berobat padapelayanan kesehatanberobat padapelayanan kesehatan
Internal Value
81
Categorical Variables Codings
20 .000 .000 .00033 1.000 .000 .00061 .000 1.000 .000
34 .000 .000 1.00017 .000 .00030 1.000 .000
101 .000 1.000
44 .000104 1.000
81 .00067 1.000
81 .00067 1.00089 .00059 1.00059 .000
89 1.000104 .000
44 1.000
umur 0-5 tahunumur 6-18 tahunumur 19-54
>= 55 tahun
umur
tidak bekerjaformalinformal
Status PekerjaanKRT
<= 5 orang> 5 orang
Jumlah ART
perempuanlaki-laki
Jenis Kelamin
<= 3 hari> 3 hari
Lama terganggu
tidak ada KSada KS
kartu sehat
tidak tamat SD
tamat SD keatas
Tingkat PendidikanKRT
desakota
tipe daerah
Frequency (1) (2) (3)Parameter coding
82
Block 0: Beginning Block
Iteration History a,b,c
202.461 -.270202.461 -.272
Iteration12
Step0
-2 Loglikelihood Constant
Coefficients
Constant is included in the model.a.
Initial -2 Log Likelihood: 202.461b.
Estimation terminated at iteration number 2 becauselog-likelihood decreased by less than .010 percent.
c.
Variables in the Equation
-.272 .166 2.686 1 .101 .762ConstantStep 0B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
83
Variables not in the Equation
.000 1 .99210.738 1 .001
.982 1 .32225.091 1 .0004.872 1 .027
12.693 1 .0006.832 2 .0336.188 1 .0135.661 1 .0175.693 3 .1284.413 1 .036.044 1 .834
2.873 1 .09050.224 11 .000
TIPE(1)JART(1)JK(1)LAGU(1)KS(1)EDUC_KRT(1)STAT_KRTSTAT_KRT(1)STAT_KRT(2)UMURUMUR(1)UMUR(2)UMUR(3)
Variables
Overall Statistics
Step0
Score df Sig.
84
Block 1: Method = Backward Stepwise (Wald)
Omnibus Tests of Model Coefficients
58.697 11 .00058.697 11 .00058.697 11 .000
-.053 1 .81858.644 10 .00058.644 10 .000
-.382 2 .82658.262 8 .00058.262 8 .000
-.328 1 .56757.934 7 .00057.934 7 .000
-.853 1 .35657.081 6 .00057.081 6 .000-6.580 3 .08750.501 3 .00050.501 3 .000
StepBlockModelStepBlockModelStepBlockModelStepBlockModelStepBlockModelStepBlockModel
Step 1
Step 2a
Step 3a
Step 4a
Step 5a
Step 6a
Chi-square df Sig.
A negative Chi-squares value indicates that theChi-squares value has decreased from theprevious step.
a.
85
Model Summary
143.763 .327 .439143.816 .327 .439144.198 .325 .437144.527 .324 .435145.380 .320 .429151.960 .289 .388
Step123456
-2 Loglikelihood
Cox & SnellR Square
NagelkerkeR Square
Hosmer and Lemeshow Test
12.313 8 .13811.051 8 .19913.360 8 .10010.699 8 .21910.242 8 .24821.275 6 .002
Step123456
Chi-square df Sig.
86
Variables in the Equation
-.115 .500 .053 1 .818 .8921.398 .509 7.551 1 .006 4.048-.323 .451 .512 1 .474 .7242.078 .466 19.923 1 .000 7.989-.424 .481 .778 1 .378 .6541.649 .519 10.102 1 .001 5.203
.429 2 .807-.597 .914 .426 1 .514 .551-.429 .784 .299 1 .584 .651
5.343 3 .148-1.049 .739 2.012 1 .156 .350
.177 .675 .069 1 .793 1.194
.279 .776 .130 1 .719 1.322-2.459 1.121 4.813 1 .028 .0861.402 .508 7.603 1 .006 4.062-.298 .439 .463 1 .496 .7422.081 .466 19.971 1 .000 8.013-.401 .470 .726 1 .394 .6701.635 .515 10.089 1 .001 5.128
.382 2 .826-.542 .880 .379 1 .538 .582-.396 .768 .265 1 .607 .673
5.432 3 .143-1.042 .739 1.990 1 .158 .353
.193 .671 .082 1 .774 1.213
.297 .772 .149 1 .700 1.346-2.553 1.043 5.994 1 .014 .0781.352 .490 7.609 1 .006 3.865-.244 .426 .328 1 .567 .7832.054 .456 20.280 1 .000 7.795-.431 .462 .872 1 .350 .6501.542 .489 9.951 1 .002 4.676
6.412 3 .093-1.070 .742 2.078 1 .149 .343
.183 .674 .074 1 .786 1.201
.421 .741 .323 1 .570 1.524-2.855 .868 10.818 1 .001 .0581.331 .488 7.427 1 .006 3.7862.090 .451 21.441 1 .000 8.084-.425 .461 .849 1 .357 .6541.528 .487 9.830 1 .002 4.608
6.621 3 .085-1.086 .737 2.172 1 .141 .338
.207 .668 .096 1 .756 1.230
.400 .735 .297 1 .586 1.492-2.967 .844 12.368 1 .000 .0511.302 .487 7.152 1 .007 3.6752.146 .448 22.948 1 .000 8.5471.672 .464 12.959 1 .000 5.322
6.068 3 .108-1.064 .729 2.130 1 .144 .345
.125 .654 .037 1 .848 1.134
.330 .722 .209 1 .648 1.391-3.180 .810 15.418 1 .000 .0421.198 .475 6.369 1 .012 3.3152.146 .432 24.705 1 .000 8.5521.551 .450 11.897 1 .001 4.714
-3.146 .590 28.466 1 .000 .043
TIPE(1)JART(1)JK(1)LAGU(1)KS(1)EDUC_KRT(1)STAT_KRTSTAT_KRT(1)STAT_KRT(2)UMURUMUR(1)UMUR(2)UMUR(3)Constant
Step1
a
JART(1)JK(1)LAGU(1)KS(1)EDUC_KRT(1)STAT_KRTSTAT_KRT(1)STAT_KRT(2)UMURUMUR(1)UMUR(2)UMUR(3)Constant
Step2
a
JART(1)JK(1)LAGU(1)KS(1)EDUC_KRT(1)UMURUMUR(1)UMUR(2)UMUR(3)Constant
Step3
a
JART(1)LAGU(1)KS(1)EDUC_KRT(1)UMURUMUR(1)UMUR(2)UMUR(3)Constant
Step4
a
JART(1)LAGU(1)EDUC_KRT(1)UMURUMUR(1)UMUR(2)UMUR(3)Constant
Step5
a
JART(1)LAGU(1)EDUC_KRT(1)Constant
Step6
a
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Variable(s) entered on step 1: TIPE, JART, JK, LAGU, KS, EDUC_KRT, STAT_KRT, UMUR.a.
87
Variables not in the Equation
.053 1 .818
.053 1 .818
.004 1 .947
.383 2 .826
.118 1 .731
.002 1 .960
.434 3 .933
.002 1 .967
.329 1 .566
.247 2 .884
.055 1 .815
.008 1 .929
.761 4 .944
.053 1 .817
.306 1 .580
.854 1 .356
.389 2 .823
.024 1 .876
.067 1 .7961.608 5 .900
.004 1 .952
.574 1 .449
.186 1 .6661.169 2 .557
.042 1 .838
.318 1 .573
6.381 3 .0946.133 1 .0131.033 1 .3091.391 1 .238
7.883 8 .445
TIPE(1)VariablesOverall Statistics
Step 2a
TIPE(1)STAT_KRT
STAT_KRT(1)STAT_KRT(2)
Variables
Overall Statistics
Step 3b
TIPE(1)
JK(1)STAT_KRTSTAT_KRT(1)STAT_KRT(2)
Variables
Overall Statistics
Step 4c
TIPE(1)JK(1)KS(1)STAT_KRT
STAT_KRT(1)STAT_KRT(2)
Variables
Overall Statistics
Step 5d
TIPE(1)
JK(1)KS(1)STAT_KRTSTAT_KRT(1)
STAT_KRT(2)UMURUMUR(1)UMUR(2)UMUR(3)
Variables
Overall Statistics
Step 6e
Score df Sig.
Variable(s) removed on step 2: TIPE.a.
Variable(s) removed on step 3: STAT_KRT.b.
Variable(s) removed on step 4: JK.c.
Variable(s) removed on step 5: KS.d.
Variable(s) removed on step 6: UMUR.e.
88
Classification Tablea
67 17 79.8
20 44 68.8
75.0
68 16 81.0
21 43 67.2
75.0
67 17 79.8
21 43 67.2
74.3
66 18 78.6
19 45 70.3
75.0
69 15 82.1
24 40 62.5
73.6
67 17 79.8
25 39 60.9
71.6
Observedtidak berobat padapelayanan kesehatanberobat padapelayanan kesehatan
Perilakupengobatan
Overall Percentagetidak berobat padapelayanan kesehatan
berobat padapelayanan kesehatan
Perilakupengobatan
Overall Percentagetidak berobat padapelayanan kesehatanberobat padapelayanan kesehatan
Perilakupengobatan
Overall Percentagetidak berobat padapelayanan kesehatanberobat padapelayanan kesehatan
Perilakupengobatan
Overall Percentagetidak berobat padapelayanan kesehatan
berobat padapelayanan kesehatan
Perilakupengobatan
Overall Percentage
tidak berobat padapelayanan kesehatanberobat padapelayanan kesehatan
Perilakupengobatan
Overall Percentage
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
tidak berobatpada
pelayanankesehatan
berobat padapelayanankesehatan
Perilaku pengobatan
PercentageCorrect
Predicted
The cut value is .500a.