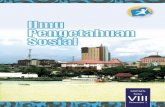Kualitas Air Sungai Code Ditinjau dari Indikator Pencemarnya
INDIKATOR INTERAKSI LINGKUNGAN HIDUPDAN PENDUDUK DI KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT
Transcript of INDIKATOR INTERAKSI LINGKUNGAN HIDUPDAN PENDUDUK DI KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT
Prosiding Pertemuan Imiah Tahunan (PIT) Ikatan Geograf Indonesia-2014
345
INDIKATOR INTERAKSI LINGKUNGAN HIDUPDAN PENDUDUK DI KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT
Oleh Rudi Iskandar
Jurusan Geografi Universitas Negeri Jakarta [email protected]
Abstrak
Penelitian ini berusaha menemukan indikator interaksi antara lingkungan hidup dan kependudukan di Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Bogor dengan unit analisis kecamatan, dari bulan Juni hingga Desember 2013. Ada 40 kecamatan yang dijadikan sampel data yang selanjutnya dijadikan dasar analisis. Penentuan variabel penelitian berdasarkan kerangka teoritis aspek Lingkungan Hidup dan kependudukan.
Metode dan Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif meliputi: mean, median, mode, frekuensi, crosstabulation, dan analisis faktor serta analisis regresi berganda.
Penelitian ini menemukan bahwa (1) Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor mengalami penurunan dengan indikator perubahan fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian. Perubahan menjadi non-pertanian khususnya permukiman dan lahan terbangun lainya. Perubahan ini terjadi di lokasi sekitar perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan dan DKI Jakarta. (2) Kondisi Lingkungan Hidup sebagian besar wilayah Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan indeks kekeringan (sangat kering hingga kering) dengan luasan hampir mencapai 95 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bogor. Hal ini menunjukkan Kabupaten Bogor bukanlah wilayah yang potensial untuk kegiatan pertanian sawah irigasi, tetapi lebih potensial untuk perkebunan, tegalan, hutan, semak, rumput atau jenis komoditi taman lahan kering lainnya. (3) Kondisi kependudukan di wilayah Kabupaten Bogor ditentukan sebagian oleh kualitas sumberdaya yang dimiliki oleh petani, kualitas penduduk (pendidikan) dan akses rumahtangga dalam menggunakan PLN serta kepadatan agraris. (4) Rumahtangga petani terbukti mengalami peningkatan sejahtera dengan indikatornya adalah maju dalam pendidikan dan lebih sejahtera (indikator penggunaan PLN), dan secara signifikan dapat mengurangi kerusakan lingkungan (melalui indikator jumlah bangunan kumuh). (5) Ada kaitan yang erat antara indikator lingkungan hidup yakni; luas lahan sawah irigasi dan semakin berkurangnya jumlah bangunan kumuh dengan indikator kependudukan (kepadatan agraris). Artinya semakin luas lahan sawah irigasi, maka semakin baik penguasaan lahan pertanian, hal ini dapat digambarkan melalui kepadatan agraris. Selanjutnya kepadatan agraris yang lebih baik (penguasaan lahan yang lebih luas) dapat mengurangi kerusakan lingkungan (jumlah bangun kumuh) di wilayah Kabupaten Bogor. (6) Di Bagian Barat wilayah Kabupaten Bogor, telah terjadi penurunan aktivitas pertanian dengan indikator semakin berkurangnya rumahtangga pertanian. Hal ini menujukkan semakin berkurangnya lahan (pertanian) yang sebelumnya dikelola rumahtangga pertanian menjadi non pertanian atau setidaknya lahan yang sementara tidak diusahakan(7) Terdapat 12 Kecamatan di Kabupaten Bogor yang mempunyai angka IPM di atas capaian Kabupaten Bogor (72,72) yaitu: Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Kemang, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Tajur Halang, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Bojonggede dan Kecamatan Ciampea. Sedangkan lima Kecamatan peringkat bawah adalah Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Cariu, Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Nanggung.
Kata kunci: Lingkungan Hidup Alamiah, Kependudukan, Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Bogor.
Prosiding Pertemuan Imiah Tahunan (PIT) Ikatan Geograf Indonesia-2014
346
PENDAHULUAN
Lingkungan hidup dan Kependudukan adalah sebuah ekosistem yang saling
berinteraksi dan tergantung satu sama lain. Kondisi kependudukan dapat dipengaruhi
oleh lingkungan hidup alamiah, dan sebaliknya. Kondisi lingkungan hidup alamiah
yang sudah mengalami degradasi, baik karena gangguan alami seperti becana
maupun campur tangan manusia seperti adanya kegiatan pembangunan, dan tidak
dapat mendukung aktivitas manusia di dalamnya, efeknya dapat mempengaruhi
kualitas penduduk. Bila tidak ada sumber daya yang lain, misalnya aktivitas di luar
pertanian atau teknologi yang dapat mengatasi kerusakan itu, kualitas penduduk
dapat berpotensi menjadi rendah. Demikian juga halnya jika kondisi kependudukan
yang ekstrim, misalnya jumlah penduduk besar, maka untuk mendukung aktivitas
penduduknya diperlukan sumber daya alam. Pengeksploitasian sumber daya alam
tanpa mengindahkan keterbatasan alam dapat merusak lingkungan hidup alamiah.
Dengan demikian bila kondisi lingkungan hidup alamiah dan kependudukan tidak
serasi, maka kualitas hidup penduduk menjadi jelek, akibatnya dapat mempengaruhi
proses pembangunan pembangunan ke depan.
Untuk meningkatkan kualitas penduduk dan sekaligus menjaga kelestarian
lingkungan hidup, maka perlu diketahui proses interaksi serta faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Dengan diketahuinya indikator interaksi dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya, maka selanjutnya dapat dibuat masukan (input) terhadap
pembangunan yang diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kegiatan
penduduk dengan kondisi lingkungan hidup agar proses pembangunan berlangsung
dengan baik dan berkelanjutan. Karena interaksi antara penduduk dan lingkungan
hidup tidak dapat diukur secara langsung, maka diperlukan indikator dari interaksi
tersebut. Indikator ini selanjutnya digunakan untuk menentukan prioritas
pembangunan wilayah yang berkelanjutan.
Patut diakui bahwa komponen pendukung interaksi penduduk dan lingkungan
hidup alamiah telah sering dimasukkan dalam analisis, tetapi belum berhasil
menentukan indikator keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup
alamiah. Tampaknya, pendekatan yang dipakai dalam analisis belum cukup
memperhatikan pemisahan antara variabel daya dukung wilayah dan variabel
keluaran sebagai hasil akhir interaksi antara kependudukan dan lingkungan hidup
alamiah. Studi ini berusaha mengisi kekosongan penjelasan itu terutama di wilayah
Kabupaten Bogor.
Kabupaten Bogor sebagai wilayah penyangga utama di bagian selatan Jakarta,
membutuhkan penanganan pengelolaan lingkungan yang baik. Penduduk adalah
komponen utama dalam pengelolaan pembangunan, sehingga sangat penting untuk
Prosiding Pertemuan Imiah Tahunan (PIT) Ikatan Geograf Indonesia-2014
347
diketahui bagaimana interaksi antara lingkungan hidup dan penduduknya. Karena
kualitas interaksi ini dapat menentukan kualitas lingkungan secara umum dan hal ini
juga akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap wilayah DKI
Jakarta. Indikator interaksi lingkungan hidup dan penduduk merupakan ukuran yang
dapat dipakai dalam menentukan tingkat perkembangan pembangunan di suatu
wilayah yang sempit. Hal inilah yang ingin diketahui oleh peneliti. Dengan
diketahuinya indikator interaksi tersebut di suatu wilayah Kabupaten Bogor), maka
dapat dipakai sebagai alternatif pemecahan masalah lingkungan hidup dan
kepenudukan dengan cara melakukan penyusunan pengembangan kebijakan seperti:
pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup dan lain-lain di suatu wilayah yang
sempit (lebih detil). Atas dasar maka masalah penelitiannya adalah sebagai berikut:
1. Apakah ada pengaruh kondisi Lingkungan Hidup terhadap Indeks Pembangunan
Manusia (kualitas penduduk) di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah ada pengaruh kondisi kependudukan terhadap Indeks Pembangunan
Manusia (kualitas penduduk) di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat?
Daya Dukung Lingkungan dan Pembangunan
Menurut Soemarwoto (2001), daya dukung lingkungan pada hakekatnya
adalah daya dukung lingkungan alamiah, yaitu berdasarkan biomas tumbuhan dan
hewan yang dapat dikumpulkan dan ditangkap per satuan luas dan waktu di daerah
itu. Menurut Khanna (1999), daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua
komponen, yaitu kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan kapasitas tampung
limbah (assimilative capacity). Kemampuan lingkungan untuk mendukung peri-
kehidupan semua makhluk hidup yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk
memenuhi kebutuhan dasar dan tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat
kestabilan sosial tertentu disebut daya dukung lingkungan. Keberadaan sumber daya
alam di bumi tidak tersebar merata sehingga daya dukung lingkungan pada setiap
daerah akan berbeda-beda. Oleh karena itu, pemanfaatanya harus dijaga agar terus
berkesinambungan dan tindakan eksploitasi harus dihindari. Pemeliharaan dan
pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional.
Menurut Lenzen (2003), kebutuhan hidup manusia dari lingkungan dapat
dinyatakan dalam luas area yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan
manusia.Luas area untuk mendukung kehidupan manusia ini disebut jejak ekologi
(ecological footprint).Lenzen juga menjelaskan bahwa untuk mengetahui tingkat
keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, kebutuhan hidup manusia
kemudian dibandingkan dengan luas aktual lahan produktif.Perbandingan antara jejak
ekologi dengan luas aktual lahan produktif ini kemudian dihitung sebagai
Prosiding Pertemuan Imiah Tahunan (PIT) Ikatan Geograf Indonesia-2014
348
perbandingan antara lahan tersedia dan lahan yang dibutuhkan. Carrying capacity
atau daya dukung lingkungan mengandung pengertian kemampuan suatu tempat
dalam menunjang kehidupan mahluk hidup secara optimum dalam periode waktu
yang panjang.Daya dukung lingkungan dapat pula diartikan kemampuan lingkungan
memberikan kehidupan organisme secara sejahtera dan lestari bagi penduduk yang
mendiami suatu kawasan.
Dengan adanya masukan teknologi irigasi misalnya, lahan yang hanya dapat
menghasilkan setahun sekali dapat diubah menjadi dua sampai tiga kali panen
setahun. Tentunya, kalau tidak ada gangguan, penghasilan masyarakat akan
meningkat dan pada gilirannya kualitas hidup meningkat. Dengan demikian teknologi
(irigasi) tidak hanya mengubah lingkungan hidup alamiah, tetapi juga mengubah daya
dukung wilayah karena irigasi dapat melipatgandakan produksi, berarti dapat
meningkatkan penghasilan yang kemudian dapat meningkatkan kualitas hidup.
Jika daya dukung wilayah dikatakan memadai, baik setelah ada perubahan
teknologi dan intervensi pembangunan, maka akan tercermin dalam kualitas hidup. Di
sisi lain teknologi juga dapat langsung mengubah kualitas hidup, misalnya penemuan
teknologi dalam bidang kesehatan dan pengobatan, sehingga kesehatan masyarakat
dan kualitas hidup menjadi baik. Ini berarti, kualitas hidup merupakan cerminan
interaksi lingkungan hidup alamiah dan kependudukan. Dengan demikian, bila suatu
wilayah kualitas hidupnya baik, maka interaksi kependudukan dan lingkungan hidup
alamiah dapat dikatakan serasi.
METODE PENELITIAN
Ada dua tahap dalam melakukan analisis data, pertama, analisis Faktor dan
kedua, adalah analisis regrasi linier berganda. Menurut J. Supranto (2010), analisis
faktor merupakan nama umum yang menunjukkan suatu kelas prosedur, utamanya
digunakan untuk mereduksi data atau meringkas, dari variabel yang banyak menjadi
sedikit variabel. Secara garis besar ada dua tipe analisa faktor, yaitu: Confirmatory
Faktor Analysis dan Exploratory Faktor Analysis. Dalam penelitian ini yang dipilih
adalah Confirmatory Faktor Analysis, yaitu: Model yang diasumsikan untuk
menggambarkan, menjelaskan atau menghitung data empirik. Konstruksi dari model
ini berdasar pada informasi yang apriori mengenai sifat dari struktur data atau isi dari
teori.Model yang diasumsikan untuk menggambarkan, menjelaskan atau menghitung
data empirik. Konstruksi dari model ini berdasar pada informasi yang apriori
mengenai sifat dari struktur data atau isi dari teori (Joreskog & Sorbon, 1989 dalam
Crowley & Fan, 1997).
Prosiding Pertemuan Imiah Tahunan (PIT) Ikatan Geograf Indonesia-2014
349
Dalam penelitian ini Confirmatory Faktor Analysis digunakan untuk
mengetahui Indikator yang selanjutnya dapat digunakan untuk melihat interaksi
antara Variabel Lingkungan Hidup dan Variabel Kependudukan di Kabupaten Bogor.
Dengan rumus sebagai berikut :
Xi = Ail F1 + Ai2 F2 + ….. Aik Fk + µi
Keterangan : Xi : item / variabel dalam faktor Ai1…Aik : konstanta faktor F1…Fk : faktor-faktor µi : faktor unik
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Faktor dan Pembahasan
1. Faktor Lingkungan Hidup
Indikator keluaran lingkungan hidup alamiah yang digunakan dalam penelitian
ini adalah aspek fisik antara lain: luas sawah (irigrasi, non irisgasi, tadah hujan dan
lahan kering lainnya), jumlah bangunan kumuh dan indeks kekeringan (sangat kering,
kering, kurang kering, tidak kering). Adapun hasil perhitungan dengan menggunakan
analisis faktor terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bogor adalah sebagai
berikut:
a. Berdasarkan tabel KMO and Barleet’s test of sphericity, besaran nilai KMO pada
faktor ketidaktahuan sebesar 0,563 artinya lebih besar dari 0,5 maka analisis
faktor tersebut dapat digunakan dan dilanjutkan.
b. Pada tabel Communalities terdapat kolom Extraction, pada kolom tersebut
diketahui nilai dari masing-masing variabel pada faktor > 0,500 yang artinya
variabel-variabel ini cukup efektif, kecuali variabel jumlah bangunan kumuh yang
sedikit di bawah 0,5.
c. Berdasarkan tabel Total Variance Explained dapat dilihat bahwa nilai eigenvalues
yang lebih dari 1 ada 3, dengan masing-masing eigenvalue sebesar 3.852 dengan
persentase sebesar 38.523%, 2.748 dengan persentase 27.480% dan 1.684
dengan persentase 16.840%.
Prosiding Pertemuan Imiah Tahunan (PIT) Ikatan Geograf Indonesia-2014
350
d. Dari tabel Component Matrix dapat diketahui terdapat 3 variabel yang
dikelompokkan. Pengelompokan variabel berdasarkan pada nilai komponen yang
menunjukkan lebih dari 0,500. Variabel yang memiliki nilai komponen lebih dari
0,500 maka variable tersebut berada pada pengelompokannya. Dari tabel rotasi
dapat dikelompokkan variabel 1 atau komponen 1 yang terdiri dari: Luas Sawah
Non-Irigasi (Ha), Luas Total Sawah (Ha), lahan kering (kebun. Tegalan, hutan,
semak, rumput/ha), Luas Sawah Tadah Hujan, Indeks Kekeringan (Proporsi Luas
Sangat Kering, Proporsi Luas Kering, Proporsi Luas Kurang Kering, Proporsi Luas
Tidak Kering) , Jumlah Bangunan Kumuh.Kumuh. Variabel 2 atau komponen 2
terdiri dari: Indeks kekeringan (Proporsi Luas Kurang Kering, Proporsi Luas Tidak
Kering) dan Jumlah Bangunan Kumuh. Sedangkan variabel 3 atau komponen 3
terdiri dari: Indeks Kekringan (proporsi luas kering) dan Luas Sawah Irigasi (Ha).
e. Setelah dilakukan Rotasi, maka pengelompokannya adalah sebagai berikut:
variabel 1 atau komponen 1 yang terdiri dari: Indeks Kekeringan (Proporsi Luas
Kering, Proporsi Luas Sangat Kering), lahan kering (kebun, tegalan, hutan, semak,
rumput/ha), Luas Sawah Non-Irigasi (Ha), Luas Sawah Tadah Hujan. Variabel 1
atau komponen 1 ini selanjutnya disebut fator Penggunaan Lahan Kering. Variabel
2 atau komponen 2 terdiri dari: Luas Sawah Tadah Hujan, Luas Sawah Irigasi (Ha),
Luas Total Sawah. Variabel 2 atau komponen 2 ini selanjutnya disebut faktor Luas
Sawah Total. Variabel 3 atau komponen 3 terdiri dari: Indeks Kekeringan
(Proporsi Luas Tidak Kering, Proporsi Luas Kurang Kering), dan Jumlah Bangunan
Kumuh. Variabel 3 atau komponen 3 ini selanjutnya disebut faktor Bangunan
Kumuh.
Dari hasil analisis faktor terhadap sekumpulan data lingkungn hidup Kabupaten
Bogor, maka dapat diketahui bahwa indikator Lingkungan Hidup di Kabupaten Bogor
(varibel 1 atau komponen 1) didominasi oleh faktor Penggunaan Lahan kering, yaitu
(proporsi luas sangat kering dan kering). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah
Kabupaten Bogor sebagian besar merupakan wilayah dengan indeks kekeringan
sangat kering hingga kering) hampir mencapai 96 persen dari seluruh luas wilayah
Kabupaten Bogor. Hal ini menunjukkan Kabupaten Bogor bukanlah wilayah yang
potensial untuk aktifitas pertanian sawah irigasi, tetapi potensial untuk perkebunan,
tegalan, hutan, semak, rumput atau jenis komoditi taman lahan kring lainnya. Oleh
karena itu peluang untuk dikonversi menjadi lahan non-pertanian (mengingat wilayah
yang dekat DKI Jakarta) menjadi cukup besar (karena larangan keras hanya berlaku
bagi wilayah yang termasuk ke dalam irigasi teknis), jika tidak dibuatkan aturan yang
lebih ketat.Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya permukiman penduduk di
wilayah Kabupaten Bogor terutama yang berdekatan dengan kota-kota seperti Kota
Prosiding Pertemuan Imiah Tahunan (PIT) Ikatan Geograf Indonesia-2014
351
Bogor, Kota Tangerang Selatan, Jakarta dan Bekasi. Pentingnya membuat aturan
terhadap larangan mengkonversi lahan pertanian, hutan, perkebunan, tegalan ke
non-pertanian ini, mengingat wilayah Kabupaten Bogor merupakan daerah
penyangga (buffer zone) yang penting bagi wilayah di bagian utaranya (DKI Jakarta).
Variabel atau komponen kedua yang menunjukkan indikator interaksi lingkungan
hidup di wilayah Kabupaten Bogor adalah Faktor luas sawah total. Komponen kedua
ini menunjukkan ada kemiripan sebagian dengan komponen pertama (seperti luas
sawah non-irigasi atau tadah hujan), hal ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan
kering merupakan indikator penting dalam intekasi lingkungan hidup di wilayah
Kabupaten Bogor.
Adapun variabel lain adalah faktor jumlah bangunan kumuh. Ada kaitan erat yang
bersifat negatif, antara luas lahan tidak kering yang mana sebagiannya merupakan
sawah irigasi dengan jumlah bangunan kumuh. Semakin luas sawah irigasi maka
jumlah bangunan kumuh akan semakin berkurang. Artinya, petani dengan
kepemilikan lahan sawah irigasi dapat mengurangi jumlah bangunan kumuh.
Sementara itu, faktor jumlah bangunan kumuh juga dapat menjelaskan kondisi
lingkungan di wilayah Kabupaten Bogor.Karena kondisi ini dapat menggambarkan
bahwa ada sebagian di wilayah Kabupaten Bogor kondisi lingkungan permukiman
penduduknya yang masih belum sehat.Mengingat ada hampir 14.000 bangunan
kumuh yang ada di Kabupaten Bogor.Tapi kondisi ini menjadi faktor yang kurang
signifikan dalam kaitannya dengan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Bogor.Tapi
walaupun demikian rumah yang kumuh dapat menggambarkan kondisi sanitasi
lingkungan yang kurang sehat.
Beberapa indikator lingkungan hidup di atas masih perlu dikembangkan
mengingat begitu kompleksnya masalah lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten
Bogor.Misalnya wilayah bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan yang
sejuk, yang mengundang pendatang dari kota-kota lain untuk berinvestasi disini,
akibatnya tidak sedikit bangunan-bangunan villa atau rumah yang tidak memenuhi
persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan.Dampaknya adalah semakin mempercepat
deforestasi sehingga mempengaruhi daerah resapan penting sebagai penyimpan air.
Sementara itu di bagian utaranya adalah wilayah endapan yang sangat potensial
bagi pertanian irigasi. Tetapi mengingat wilayah ini sangat dekat dengan kota-kota
besar (KotaDepok, Kota Bogor dan Jakarta) maka yang menjadi tantangannya adalah
dikonversi menjadi permukiman, mengingat permintaan yang sangat besar bagi orang
yang bekerja di Jakarta dan sekitarnya tetapi tidak mampu berinvestasi lahan di
Jakarta (mengingat harga lahan yang sangt mhal). Hal ini dibuktikan terutama di
wilayah Kecamatan Ciomas, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Cibinong dan
Prosiding Pertemuan Imiah Tahunan (PIT) Ikatan Geograf Indonesia-2014
352
Kecamatan Gunung Putri yang mengalami kepadatan penduduk yang tinggi di
Kabupaten Bogor. Di wilayah tersebut tumbuh subur pembangunan perumahan
menengah ke bawah, sehingga banyak diminati kelompok pekerja dengan
pendapatan menengah ke bawah.
2. Faktor Kependudukan
Kabupaten Bogor adalah salah satu Kabupaten di propinsi Jawa Barat yang pada
tahun 1990 mempunyai penduduk sebesar 3.736.897 jiwa.Pada tahun 2000 turun
menjadi 3.508.826 jiwa.Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk
Kabupaten Bogor mencapai 4.771.932 jiwa.Penurunan jumlah penduduk Kabupaten
Bogor karena pada tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi
Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Sebagian wilayah di Kabupaten Bogor yang
menjadi bagian dari Kota Depok, yaitu: Kecamatan Beji, Kecamatan Sukmajaya,
Kecamatan Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Limo, dan Kecamatan
Cimanggis.
Dengan rumus baku laju pertumbuhan penduduk, maka didapatan laju
pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor periode 1990-2000, cederung mengalami
penurunan (0,63%) sedangkan laju pertumbuhan penduduk periode 2000-2010
sebesar 3,15%. Dari hasil sensus penduduk tahun 2010 yang dibandingkan dengan
luas wilayah Kabupaten Bogor didapatkan kepadatan penduduk sebesar 17,91 jiwa
perhektar ini berarti, terdapat 1.791 orang untuk area dengan luas 1 km persegi.
Dengan demikian kepadatan penduduk disuatu wilayah implikasinya semakin berat
permasalahan yang harus dihadapi pemerintah daerah setempat.Besarnya populasi di
Kabupaten Bogor ini diharapkan bukan lagi sebagai beban pembangunan tetapi lebih
sebagai asset pembangunan.
Indikator Kependudukan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Jumlah
Rumahtangga Pertanian (2013), Pertumbuhan rumahtangga pertanian (RTP) Antara
tahun 2003-2013, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah,
Rumahtangga Pengguna Perusahaan Listrik Negara (PLN), Rumahtangga Non
Pengguna PLN, Jumlah Keluarga Petani, Jumlah Rumahtangga yang ada buruh tani,
Kepadatan Agraris, Proporsi Rumahtangga Petani terhadap Rumahtangga Total.
Adapun hasil perhitungan dengan menggunakan analisis faktor terhadap
kependudukan di Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:
a. Berdasarkan tabel KMO and Barleet’s test of sphericity, besaran nilai KMO pada
faktor ketidaktahuan sebesar 0,647 artinya lebih besar dari 0,5 maka analisis
faktor tersebut dapat digunakan dan dilanjutkan.
Prosiding Pertemuan Imiah Tahunan (PIT) Ikatan Geograf Indonesia-2014
353
b. Pada tabel Communalities terdapat kolom Extraction, pada kolom tersebut
diketahui nilai dari masing-masing variabel pada faktor > 0,500 yang artinya
variabel-variabel ini cukup efektif.
c. Berdasarkan tabel Total Variance Explained dapat dilihat bahwa nilai eigenvalues
yang lebih dari 1 ada 4, dengan masing-masing eigenvalue sebesar 4.473 dengan
persentase sebesar 40.667%, 1.445 dengan persentase 53.801% dan 1.356 dengan
persentase 66.125%, 1.139 dengan persentase 76.484%.
d. Dari tabel Component Matrix dapat diketahui terdapat 4 variabel yang
dikelompokkan. Pengelompokan variabel berdasarkan pada nilai komponen yang
menunjukkan lebih dari 0,500. Variabel yang memiliki nilai komponen lebih dari
0,500 maka variable tersebut berada pada pengelompokannya. Dari tabel rotasi
dapat dikelompokkan variabel 1 atau komponen 1 yang terdiri dari: Rata-rata
Lama Sekolah, Proporsi Rumahtangga Petani terhadap Rumahtangga Total,
Jumlah Rumahtangga Pertanian (2013), Jumlah Rumahtangga yang ada buruh
tani, Jumlah Keluarga Petani, Angka Melek Huruf. Dan Rumahtangga Pengguna
PLN.
Variabel 2 atau komponen 2 terdiri dari : Angka Harapan Hidup, Kepadatan
Agraris. Variabel 3 atau komponen 3 terdiri dari: Rumahtangga Non Pengguna
PLN, Pertumbuhan Rumahtangga Pertanian, Angka Harapan Hidup. Variabel 4
atau komponen 4 teridir dari: Jumlah Keluarga Petani.
e. Setelah dilakukan Rotasi, maka pengelompokannya adalah sebagai berikut:
variabel 1 atau komponen 1 yang terdiri dari: Jumlah Keluarga Petani, Proporsi
Rumahtangga Petani terhadap Rumahtangga Total, Jumlah Rumahtangga
Pertanian (2013), Jumlah Rumahtangga yang ada buruh tani.Variabel 1 atau
komponen 1 ini selanjutnya disebut faktor Kuantitas Petani dan buruh tani.
Variabel 2 atau komponen 2 terdiri dari : Rata-rata Lama Sekolah, Rumahtangga
Pengguna PLN, Angka Melek Huruf, Kepadatan Agraris. Variabel 2 atau komponen 2
ini selanjutnya disebut faktor Kesejahteraan Penduduk. Variabel 3 atau komponen 3
terdiri dari: Angka Harapan Hidup dan Pertumbuhan Rumahtangga Pertanian, KK non
Pengguna PLN selanjutnya disebut faktor pertumbuhan RTP (2003-2013)
Dari hasil analisis faktor di atas dengan melakukan rotasi, maka dapat diketahui
bahwa kondisi kependudukan wilayah Kabupaten Bogor didominasi oleh indikator
Kuantitas Petani dan buruh tani (Jumlah Keluarga Petani, Proporsi rumanhtangga
Petani terhadap rumahtangga seluruh penduduk Kabupaten Bogor (total), Jumlah
Rumahtangga Pertanian (2013), Jumlah rumahtangga yang ada buruh tani). Hal ini
menunjukkan bahwa komponen kuantitas petani dan buruh tani merupakan faktor
yang menjadi indikator interaksi kependudukan di wilayah Kabupaten Bogor.
Prosiding Pertemuan Imiah Tahunan (PIT) Ikatan Geograf Indonesia-2014
354
Variabel atau komponen lain yang muncul sebagai indikator interaksi
kependudukan di Wilayah Kabupaten Bogor adalah Rata-rata Lama Sekolah
penduduk, jumlah rumahtangga yang menggunakan Perusahaan Listrik Negara (PLN),
Angka Melek Huruf penduduk, Kepadatan Agraris (banyaknya rumahtangga petani
pada setiap hektar lahan pertanian). Variabel atau komponen kedua ini lebih
bervariasi dimana, aspek pendidikan penduduk (Rata-rata Lama Sekolah dan Angka
Melek Huruf) cukup dominan pada variabel atau komponen kedua ini, selain faktor
banyaknya keluarga yang menggunakan PLN dan kepadatan agraris. Ada kaitan yang
erat antara tingkat pendidikan penduduk dengan penggunaan Perusahaan Listrik
Negara (PLN), semakin tinggi pendidikan penduduk, maka semakin cenderung untuk
menggunakan fasilitas PLN. Hal yang sama dengan kepadatan agraris, artinya di
wilayah yang kepadatan agrarisnya lebih besar (penguasaan rumahtangga terhadap
luas lahan pertanian sawah), maka memiliki kecenderungan pendidikan di
keluarganya lebih baik dan cenderung menggunakan fasilitas listrik negara (PLN). Hal
ini menunjukkan kondisi keluarga petani sudah lebih maju dibidang pendidikan
sehingga lebih rasional dalam memanfaatkan listrik. Pemanfaatan listrik sebagai
kebutuhan dasar ini tentu memiliki efek multiplier (efek pengganda), artinya akan
cenderung memaksimalkan fasilitas ini seperti membeli kebutuhan tersier lainnya
(televisi, kulkas, magicom dan kebutuhan rumahtangga yang berbasis listrik lainnya).
Artinya, penggunaan listrik ini akan merangsang penduduk untuk memiliki kebutuhan
lain yang lebih banyak. Bahkan rekening tagihan listrik dapat dijadikan ukuran bahwa
sebuah rumahtangga itu lebih mapan.Sehingga variabel atau komponen yang kedua
ini lebih tepat disebut sebagai faktor kesejahteraan atau standar hidup layak.
Variabel atau komponen berikutnya yang muncul sebagai indikator interaksi
kependudukan di wilayah Kabupaten Bogor adalah Angka Harapan Hidup, KK Non
pengguna PLN dan Pertumbuhan Rumahtangga Pertanian (RTP) Antara tahun 2003 –
2013. Dimana sifat hubungannya adalah negatif, artinya semakin baik Angka Harapan
Hidup penduduk Kabupaten Bogor ternyata pertumbuhan Rumahtangga Pertaniannya
terjadi sebaliknya yaitu semakin menurun. Hal ini dapat pula diartikan bahwa jumlah
rumahtangga pertanian sekarang ini (walaupun jumlahnya menurun), tapi memiliki
kualitas yang lebih baik.
Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas
yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam
hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf (AMH) ini dapat : (1) mengukur keberhasilan
program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan dimana
masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD; (2)
menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari
Prosiding Pertemuan Imiah Tahunan (PIT) Ikatan Geograf Indonesia-2014
355
berbagai media; (3) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan
tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan
intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Secara keseluruhan, walaupun terjadi penurunan jumlah Rumahtangga
pertanian dari tahun 2003-2013, tapi kualitas rumahtangga petani mengalami
peningkatan setidaknya dari aspek Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf,
meskipun rata-rata lama sekolah yang lebih panjang. Kesejahteraan petani juga
meningkat dengan semakin banyaknya rumahtangga yang mengakses PLN. Hal ini
merupakan kemajuan yang cukup signifikan mengingat selama ini lokasi rumahtangga
petani yang tersebar diberbagai pelosok wilayah, bahkan di balik perbukitan karena
wilayah Kabupaten Bogor yang sebagian besar bertopografi kasar (berbukit).
Fenomena menarik lain dari faktor kependuduan di wilayah Kabupaten Bogor adalah
rumahtangga petani yang tetap bertahan ternyata bisa meningkatkan
kesejahteraannya. Tantangan penelitian berikutnya adalah apakah rumahtangga
pertanian yang beralih ke non-pertanian mengalami hal yang sama atau bahkan
sebaliknya, kesejahteraannya semakin menurun.
Analisis Regresi dan Pembahasan
Untuk melihat apakah ada pengaruh sebagai akibat dari interaksi Lingkungan
Hidup dan Kependudukan, maka dilakukan analisis regresi.Analisis regresi ini
dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari analisis faktor yang sebelum sudah dilakukan.
Setelah dilakukan analisis regresi linier berganda terhadap pengelompokan variabel
lingkungan idup, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Analisis Regresi Linier Berganda Untuk Lingkungan Hidup Terhadap Indeks Pembanguan Manusia (IPM)
Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya
pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan demikian yang
dicari adalah pengaruh variabel bebas (independen variable) yaitu faktor
Penggunaan Lahan Kering (X1), faktor Luas Sawah Total (X2), faktor Bangunan
Kumuh(X3) terhadap variabel terikat (dependen variable) yaitu Indeks
Pembangunan Manusia (Y).
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Dimana: Y = Indeks Pembangunan Manusia (Y) A = Konstanta b1,b2,b3 = Koefisien determinasi
X1 = faktor Penggunaan Lahan Kering X2 = faktor Luas Sawah Total X3 = faktor Bangunan Kumuh E = Error
Prosiding Pertemuan Imiah Tahunan (PIT) Ikatan Geograf Indonesia-2014
356
Adapun hasil pengolahan hasil dengan SPSS versi 22terhadap persamaan regresinya
adalah sebagai berikut: Correlations
Indeks Pembangunan
Manusia
faktor Penggunaan Lahan Kering
faktor Luas Sawah Total
faktor Bangunan
Kumuh
Pearson Correlation Indeks Pembangunan Manusia 1.000 -.613 -.402 -.042
fator Penggunaan Lahan Kering -.613 1.000 .000 .000 faktor Luas Sawah Total -.402 .000 1.000 .000 faktor Bangunan Kumuh -.042 .000 .000 1.000
Sig. (1-tailed) Indeks Pembangunan Manusia . .000 .005 .399 fator Penggunaan Lahan Kering .000 . .500 .500 faktor Luas Sawah Total .005 .500 . .500 faktor Bangunan Kumuh .399 .500 .500 .
N Indeks Pembangunan Manusia 40 40 40 40 fator Penggunaan Lahan Kering 40 40 40 40 faktor Luas Sawah Total 40 40 40 40 faktor Bangunan Kumuh 40 40 40 40
Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut:
Y = 1.000 – 0.613 X1 - 0,402 X2 - 0,042 X3 + e
Interpretasi dari regresi diatas adalah sebagai berikut:
1. Konstanta (a)
Ini berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat
(Indeks Pembangunan Manusia) sebesar 1.0.
2. Faktor Penggunaan Lahan Kering (X1) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)
Nilai koefisien faktor Penggunaan Lahan Kering untuk variabel X1 sebesar -0.613.
Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Penggunaan Lahan Kering satu
satuan maka variabel IPM (Y) akan turun sebesar -0.613 dengan asumsi bahwa
variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
3. Faktor Luas Sawah Total (X2) terhadap IPM (Y)
Nilai koefisien Faktor Penggunaan Lahan untuk variabel X2 sebesar -0,402 dan
bertanda negatif, ini menunjukkan bahwa Faktor Penggunaan Lahan mempunyai
hubungan yang berlawanan arah dengan IPM. Hal ini mengandung arti bahwa
setiap kenaikan Faktor Penggunaan Lahan satu satuan maka variabel IPM (Y) akan
turun sebesar 0,402 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model
regresi adalah tetap.
4. Faktor Bangunan Kumuh (X3) terhadap IPM (Y)
Nilai koefisien Faktor Bangunan Kumuh terstandarisasi untuk variabel X3 sebesar -
0,042 dan bertanda negatif, ini menunjukkan bahwa Faktor Bangunan Kumuh
mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan IPM. Hal ini mengandung arti
bahwa setiap kenaikan Faktor Bangunan Kumuh satu satuan maka variabel IPM (Y)
akan turun sebesar 0,023 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari
model regresi adalah tetap.
Prosiding Pertemuan Imiah Tahunan (PIT) Ikatan Geograf Indonesia-2014
357
Untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial
berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen maka dilakukan dengan Uji
t. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil
dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan
bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.
Analisis uji t juga dilihat dari tabel ”Coefficient” di bawah ini:
Coefficients
a
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
Correlations Collinearity Statistics
B Std. Error Beta
Zero-order Partial Part
Tolerance VIF
1 (Constant) 71.439 .288 248.174 .000
(faktor penggunaan lahan kering)
-1.582 .292 -.613 -5.427 .000 -.613 -.671 -.613 1.00 1.00
(faktor luas sawah total)
-1.038 .292 -.402 -3.559 .001 -.402 -.510 -.402 1.00 1.00
(faktor Bangunan Kumuh)
-.108 .292 -.042 -.371 .713 -.042 -.062 -.042 1.00 1.00
a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia
1. Faktor penggunaan lahan kering (X1) terhadap IPM (Y)
Terlihat pada kolom Coefficients model 1 terdapat nilai sig 0,000. Nilai sig lebih
kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,000<0,05, maka H1 diterima dan Ho
ditolak. Variabel X1 mempunyai thitung yakni 5.427 dengan ttabel = 2,021. Jadi
thitung>ttabel atau -thitung<-ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki
kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai
hubungan yang berlawanan arah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan Faktor
penggunaan lahan kering memiliki pengaruh signifikan (berlawanan arah)
terhadap IPM.
2. Faktor luas sawah total (X2) terhadap IPM (Y)
Terlihat pada kolom Coefficients model 1 terdapat nilai sig 0,001. Nilai sig lebih
kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,001<0,05, maka H1 diterima dan Ho
ditolak. Variabel X2 mempunyai thitung yakni 3,559 dengan ttabel=2,021. Jadi
thitung>ttabel atau -thitung<-ttabeldapat disimpulkan bahwa variabel X2 memiliki
kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa X2 mempunyai
hubungan yang berlawanan arah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan Faktor luas
sawah total memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM.
3. Faktor Bangunan Kumuh (X3) terhadap IPM (Y)
Terlihat nilai sig untuk Faktor Bangunan Kumuh adalah 0,713. Nilai sig lebih besar
dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,713>0,05, maka H1 ditolak dan Ho
Prosiding Pertemuan Imiah Tahunan (PIT) Ikatan Geograf Indonesia-2014
358
diterima. Variabel X3 mempunyai thitung yakni 0,371 dengan ttabel=2,021. Jadi
thitung<ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel X3 tidak memiliki kontribusi
terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa X3 mempunyai hubungan yang
berlawanan arah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan Faktor Bangunan Kumuh tidak
berpengaruh signifikan terhadap risiko IPM.
Untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen maka perlu dilakukan uji F.
Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan
lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan
bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
variabel dependen. Untuk analisisnya dari output SPSS dapat dilihat dari tabel
”Anova”, ANOVA
a
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 140.072 3 46.691 14.087 .000b
Residual 119.323 36 3.315
Total 259.395 39
a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia
b. Predictors: (Constant), faktor Bangunan Kumuh , faktor Luas Sawah Total, fator Penggunaan
Lahan Kering
Pengujian secara simultan X1, X2, dan X3 terhadap Y:
Dari tabel diperoleh nilai Fhitung sebesar 14.087 dengan nilai probabilitas
(sig)=0,000. Nilai Fhitung(14.087)>Ftabel (2,61), dan nilai sig. lebih kecil dari nilai
probabilitas 0,05 atau nilai 0,000<0,05; maka H1 diterima, berarti secara bersama-
sama (simultan) X1 faktor Penggunaan Lahan Kering,faktor Luas Sawah Total, faktor
Bangunan Kumuh berpengaruh signifikan terhadap IPM.
Untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam
pengertian yang lebih jelas maka digunakan koefisien Determinasi. Koefisien
determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel
bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain. Dalam bahasa
sehari-hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel
terikatnya dalam satuan persentase.
Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat
terbatas.Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel dependen. Untuk analisisnya dengan menggunakan output SPSS versi 22.0
dapat dilihat pada tabel ”Model Summary”.
Prosiding Pertemuan Imiah Tahunan (PIT) Ikatan Geograf Indonesia-2014
359
Berdasarkan Tabel ”Model Summary” dapat disimpulkan bahwa faktor
Penggunaan Lahan Kering,faktor Luas Sawah Total, faktor Bangunan Kumuh
berpengaruh sebesar 54% terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan
46% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Karena nilai R Square di atas 50%
atau cenderung mendekati nilai 1 maka dapat disimpulkan kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel cukup kuat.
Model Summary
b
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
Change Statistics
R Square
Change F Change df1 df2
Sig. F
Change
1 .735a .540 .502 1.82059 .540 14.087 3 36 .000
a. Predictors: (Constant), faktor Bangunan Kumuh , faktor Luas Sawah Total, fator Penggunaan Lahan Kering
b. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia
2. Analisis Regresi Linier Berganda Faktor Kependudukan Terhadap Indeks Pembanguan Manusia (IPM)
Dengan demikian yang dicari adalah pengaruh variabel bebas (independen
variable) yaitu faktor Kuantitas Petani dan buruh tani (X1), faktor Kesejahteraan
Penduduk (X2), faktor KK Non-PLN(X3) terhadap variabel terikat (dependen variable)
yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Y).
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Dimana: Y = Indeks Pembangunan Manusia (Y) a = Konstanta b1,b2,b3 = Koefisien determinasi X1 = faktor Kuantitas Petani dan buruh tani X2 = faktor Kesejahteraan Penduduk X3 = faktor KK Non-PLN E = Error
Adapun hasil pengolahan hasil dengan SPSS versi 22.0 terhadap persamaan
regresinya adalah sebagai berikut: Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh rumus
regresi sebagai berikut:
Y = 1.000 – 0.497 X1 + 0,766 X2 - 0,012 X3 + e
Interpretasi dari regresi diatas adalah sebagai berikut:
Prosiding Pertemuan Imiah Tahunan (PIT) Ikatan Geograf Indonesia-2014
360
1. Konstanta (a) : Ini berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai
variabel terikat (Indeks Pembangunan Manusia) sebesar 1.000. Correlations
Indeks Pembangunan
Manusia
faktor Kuantitas Petani dan buruh
tani
faktorKesejah teraan
Penduduk faktorpertumbuhan RTP
Pearson Correlation
Indeks Pembangunan Manusia 1.000 -.497 .766 -.012 faktor Kuantitas Petani dan buruh tani
-.497 1.000 .000 .000
faktor Kesejahteraan Penduduk .766 .000 1.000 .000 faktor KK Non-PLN -.012 .000 .000 1.000
Sig. (1-tailed) Indeks Pembangunan Manusia . .001 .000 .471 faktor Kuantitas Petani dan buruh tani
.001 . .500 .500
faktor Kesejahteraan Penduduk .000 .500 . .500 faktor KK Non-PLN .471 .500 .500 .
N Indeks Pembangunan Manusia 40 40 40 40
faktor Kuantitas Petani dan buruh tani
40 40 40 40
faktor Kesejahteraan Penduduk 40 40 40 40 faktor KK Non-PLN 40 40 40 40
2. Faktor Kuantitas Petani dan buruh tani (X1) terhadap IPM (Y).
Nilai koefisien Faktor Kuantitas Petani dan buruh tani X1 sebesar -0.497. Hal ini
mengandung arti bahwa setiap kenaikan Penggunaan Lahan Kering satu satuan
maka variabel IPM (Y) akan turun sebesar 0.497 dengan asumsi bahwa variabel
bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
3. Faktor Kesejahteraan Penduduk (X2) terhadap IPM (Y)
Nilai koefisien Faktor Penggunaan Lahan untuk variabel X2 sebesar 0,766, ini
menunjukkan bahwa Faktor Kesejahteraan Penduduk mempunyai hubungan yang
positif dengan IPM. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Faktor
Kesejahteraan Penduduk satu satuan maka variabel IPM (Y) akan naik sebesar
0,766 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah
tetap.
4. Faktor KK Non-PLN (X3) terhadap IPM (Y)
Nilai koefisien Faktor KK Non-PLN terstandarisasi untuk variabel X3 sebesar -0,012
dan bertanda negatif, ini menunjukkan bahwa Faktor KK Non-PLN mempunyai
hubungan yang berlawanan arah dengan IPM. Hal ini mengandung arti bahwa
setiap kenaikan Faktor KK Non-PLN satu satuan maka variabel IPM (Y) akan turun
sebesar 0,012 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi
adalah tetap. Untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen maka perlu dilakukan
uji F. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil
perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif,
yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh
Prosiding Pertemuan Imiah Tahunan (PIT) Ikatan Geograf Indonesia-2014
361
signifikan terhadap variabel dependen. Untuk analisisnya dari output SPSS versi 22
dapat dilihat dari tabel ”Anova” Pengujian secara simultan X1, X2, dan X3 terhadap
Y:
Dari tabel diperoleh nilai Fhitung sebesar 44.189 dengan nilai probabilitas
(sig)=0,000. Nilai Fhitung(44.189)>Ftabel (2,61), dan nilai sig. lebih kecil dari nilai
probabilitas 0,05 atau nilai 0,000<0,05; maka H1 diterima, berarti secara bersama-
sama (simultan)
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 216.522 4 54.130 44.189 .000b
Residual 42.874 35 1.225
Total 259.395 39
a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia
b. Predictors: (Constant), faktor KK Non-PLN, faktor Kesejahteraan Penduduk, , faktor Kuantitas Petani
dan buruh tani.
faktor Kuantitas Petani dan buruh tani (X1), faktor Kesejahteraan Penduduk
(X2), faktor KK Non-PLN (X3) berpengaruh signifikan terhadap IPM (X3).
Untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam
pengertian yang lebih jelas maka digunakan koefisien Determinasi. Koefisien
determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel
bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain.
Dalam bahasa sehari-hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi
terhadap variabel terikatnya dalam satuan persentase.
Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat
terbatas.Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel dependen. Untuk analisisnya dengan menggunakan output SPSS dapat dilihat
pada tabel ”Model Summary”.
Model Summary
b
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
Change Statistics
R Square
Change F Change df1 df2
Sig. F
Change
1 .914a .835 .816 1.10678 .835 44.189 4 35 .000
a. Predictors: (Constant), faktor KK Non-PLN, faktor Kesejahteraan Penduduk
, faktor Kuantitas Petani dan buruh tani.
b. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia
Prosiding Pertemuan Imiah Tahunan (PIT) Ikatan Geograf Indonesia-2014
362
Berdasarkan Tabel ”Model Summary” dapat disimpulkan bahwa faktor
Kuantitas Petani dan buruh tani,faktor Kesejahteraan Penduduk, faktor KK Non-
PLNberpengaruh sebesar 83,5% terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
sedangkan 16,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Karena nilai R Square
mendekati nilai 1 maka dapat disimpulkan kemampuan variabel-variabel independen
dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah kuat.
SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor terus mengalami penurunan
dengan indikator terjadinya secara terus menerus perubahan fungsi lahan dari
pertanian ke non-pertanian. Perubahan menjadi non-pertanian khususnya
permukiman dan lahan terbangun lainya, terjadi di sekitar perbatasan
Kabupaten Bogor dengan Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan
dan DKI Jakarta.
2. Kondisi Lingkungan Hidup sebagian besar wilayah Kabupaten Bogor
merupakan wilayah dengan indeks kekeringan sangat kering hingga kering)
dengan luasan hampir mencapai 95 persen dari seluruh luas wilayah
Kabupaten Bogor. Hal ini menunjukkan Kabupaten Bogor bukanlah wilayah
yang potensial untuk kegiatan pertanian sawah irigasi, tetapi lebih potensial
untuk perkebunan, tegalan, hutan, semak, rumput atau jenis komoditi taman
lahan kering lainnya.
3. Kondisi kependudukan di wilayah Kabupaten Bogor ditentukan sebagian besar
oleh sumberdaya petani, kualitas penduduk (pendidikan) dan akses
rumahtangga dalam menggunakan PLN serta kepadatan agraris.
4. Faktor lingkungan Hidup (faktor Penggunaan Lahan Kering,faktor Luas Sawah
Total, faktor Bangunan Kumuh) berpengaruh cukup kuat (sebesar 54%)
terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sisanya ditentukan oleh faktor
yang yang tidak diteliti disini.
5. Faktor kependudukan (faktor Kuantitas Petani dan buruh tani,faktor
Kesejahteraan Penduduk, faktor KK Non-PLN) berpengaruh sebesar 83,5%
terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sisanya ditentukan oleh faktor
yang yang tidak diteliti disini.
6. Di Bagian Barat wilayah Kabupaten Bogor, telah terjadi penurunan aktivitas
pertanian dengan indikator semakin berkurangnya rumahtangga pertanian.
Hal ini menujukkan semakin berkurangnya lahan (pertanian) yang sebelumnya
Prosiding Pertemuan Imiah Tahunan (PIT) Ikatan Geograf Indonesia-2014
363
dikelola rumahtangga pertanian menjadi non pertanian atau setidaknya lahan
yang sementara tidak diusahakan.
7. Terdapat 12 Kecamatan di Kabupaten Bogor yang mempunyai angka IPM di
atas capaian IPM Kabupaten Bogor (72,72) yaitu: Kecamatan Gunung Putri,
Kecamatan Cibinong, Kecamatan Kemang, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan
Tajur Halang, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Citeureup, Kecamatan
Dramaga, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan
Bojonggede dan Kecamatan Ciampea. Sedangkan lima Kecamatan peringkat
bawah adalah Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Cariu,
Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Nanggung.
DAFTAR PUSTAKA
BPS Kabupaten Bogor. 2012. Kabupaten dalam Angka. Kabupaten Bogor.
BPS Kabupaten Bogor. 2010. Kabupaten dalam Angka. Kabupaten Bogor.
BPS. 2010. Kecamatan dalam Angka. Kabupaten Bogor.
Hufschmidt, Maynard M dkk. 1996. Lingkungan, Sistem Alami, dan Pembangunan (Pedoman Penilaian Ekonomi). Gadjah Mada University Press Yogyakarta.
Indonesia. 2010. Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi dan Konservasi lahan. Jakarta.
IPM Kecamatan Kabupaten Bogor 2012, Kerjasama Bappeda Kabupaten Bogor dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor
Iskandar, Rudi. 2010. Perilaku Rumahtangga dalam Pengelolaan Limbah Domestik. Kasus Desa-desa Wilayah Jakarta, Depok dan Bogor Sepanjang Aliran Sungai Ciliwung. Disertasi S-3 Program Studi: Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB.
Kunkle, S.H dan Thames, J.L.. 1976. Hydrological techniques for upstrearn conservation. New York: Forest Resources Division, Forestry Department.
MacDonald, Peter F dan Alip Sontosudarmo. 1974. Response to population pressure; the case study of special region of Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Moos, Rudolf, H.,1976, The Human Context: Environmental Determinants of Behavior, Toronto, A VViley Interscience Publication.
Muta’ali, Lutfi. 2013. Pengembangan Wilayah Perdesaan (perspektif Keruangan). Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
Muta’ali, Lutfi. 2012. Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
Odum, Eugene P. 1996. Dasar-Dasar Ekologi. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
Prosiding Pertemuan Imiah Tahunan (PIT) Ikatan Geograf Indonesia-2014
364
Redclift, Michael. 1987. Sustainable Development: Exploring The Contradiction. New York: Routledge, NY 10001.
Sajogyo. 1991. Indeks Mutu Hidup. Bogor: Pertemuan Kerja PPL Perkembangan Penduduk Indonesia PJPT I.
Sharma, P.D., 1981, Element of Ecology, foreword by R. Misra. 4 rd. ed. India: Rastologi Publication.
Sitorus, S.R.P. 1985. Evaluasi sumberdaya lahan. Bandung: Tarsito.
Soemarwoto, Otto. 1987. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan.
Suratmo, F Gunarwan. 2002. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
United Nations Funds and Population Activities (UNFPA). 1991. "Population and the Enviroument: Issues, Prospects and Policies", Kumpulan Makalah pada Diskusi Population And Environment, New York, 4-5 Maret.
Universitas Gadjah Mada. Pusat Penelitian Kependudukan. 1989. Faktor-Faktor Keserasian Kualitas Kependudukan dan Lingkungan di Bengkulu, Kalimantan Selatan dan Bali. Yogyakarta. 1989.
WCED. 1987. Our Common Future. Oxford Univ. Press. New York
Wikipedia, 2012. Indeks Pembangunan Manusia. (www.wikipedia.com)