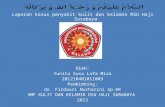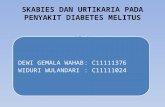Scabies
-
Upload
putra-mahautama -
Category
Documents
-
view
147 -
download
0
description
Transcript of Scabies
BAB 1PENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangKulit adalah organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Luas kulit orang dewasa 1.5 m2 dengan berat kira-kira 15 % berat badan. Kulit merupakan organ yang esensial dan vital serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Kulit juga sangat kompleks, elastis, dan sensitif, bervariasi pada keadaan iklim, umur, seks, ras, dan juga bergantung pada lokasi tubuh. Warna kulit berbeda-beda, dari kulit yang berwarna terang (fair skin ), pirang, dan hitam, warna merah muda pada telapak kaki dan tangan bayi, serta warna hitam kecoklatan pada genitalia orang dewasa. Demikian pula kulit bervariasi mengenai kelembutan, tipis, dan tebalnya. Kulit yang elastis dan longgar terdapat pada palpebra, bibir, dan preputium, kulit yang tebal dan tegang terdapat di telapak kaki dan tangan orang dewasa. Kulit yang tipis terdapat pada muka, yang lembut pada leher dan badan, dan yang berambut kasar terdapat pada kepala (Djuanda, 2007).Kulit dapat mudah dilihat dan diraba, hidup dan menjamin kelangsungan hidup. Kulit pun menyokong penampilan dan kepribadian seseorang. Kulit melindungi tubuh dari bahan dan pengaruh pencedera dengan cara menghalangi serangan mikroorganisme, membantu pengaturan suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat dan berbagai limbah katabolisme, dan menjadi organ pengindera yang luas bagi tubuh untuk menerima rangsangan raba, suhu, dan nyeri (Leeson, 1996).Kulit manusia tidak bebas hama (steril), kulit steril hanya didapatkan pada waktu yang sangat singkat setelah lahir. Bahwa kulit manusia tidak steril mudah dimengerti oleh karena permukaan kulit mengandung banyak bahan makanan (nutrisi) untuk pertumbuhan organisme, antara lain, lemak, bahan-bahan yang mengandung nitrogen, mineral, dan lain-lain yang merupakan hasil tambahan proses keratinisasi atau yang merupakan hasil apendiks kulit. Mengenai hubungannya dengan manusia, bakteri dapat bertindak sebagai parasit yang menimbulkan penyakit, atau sebagai komensal yang merupakan flora normal (Djuanda, 2007).Berbagai jenis penyakit kulit mulai dipelajari secara sistematik setelah PLENCK (1776) menulis bukunya yang berjudul System der Hautkrankheiten. Sampai kini pemikiran itu masih dipakai sebagai dasar membuat diagnosis penyakit kulit secara klinis, walaupun ditambah dengan segala kemajuan dibidang bakteriologi, mikologi, histopatologi, dan imunologi. Ada banyak jenis penyakit kulit yang bisa ditemukan dan bisa disebabkan oleh berbagai organisme baik itu virus, jamur, parasit, dan berbagai jenis alergi yang bisa menyebabkan kelainan pada kulit. Salah satu penyakit kulit yang banyak terdapat dimasyarakat adalah skabies yang merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi parasit (Djuanda, 2007).Skabies merupakan penyakit endemi pada banyak masyarakat. Penyakit ini dapat mengenai semua ras dan golongan di seluruh dunia. Penyakit ini banyak dijumpai pada anak dan orang dewasa muda, tetapi dapat juga mengenai semua umur. Insidensi sama pada pria dan wanita ( Harahap, 2000 ).Gejala klinis dari penyakit ini sudah diketahui selama lebih dari 2500 tahun yang lalu. Penyakit ini pertama kali diuraikan oleh dokter Abumezan Abdel Malek bin zaher dengan menggunakan istilah soab sebagai sesuatu yang hidup pada kulit dan menyebabkan gatal. Pada tahun 1687 Giovan Cosino Bonomo menemukan kutu sakbis pertama kali sebagai little bladder of water dari lesi skabies pada anak seorang perempuan miskin. Dan Von Hebra pada abad XIX telah melukiskan tentang pengatahuan dasar dari penyakit ini. (http://ojs.lib.unair.ac.id).
Menurut Departemen Kesehatan RI prevalensi skabies di puskesmas selurauh Indonesia pada tahun 1986 adalah 4,6 % - 12,95 % dan skabies menduduki urutan ketiga dari 12 penyakit kulit tersering. Di bagian Kulit dan Kelamin FKUI/RSCM pada tahun 1988, dijumpai 704 kasus skabies yang merupakan 5,77 % dari seluruh kasus baru. Pada tahun 1989 dan 1990 prevalensi skabies adalah 6 % dan 3,9 % (http://www.litbang.depkes.go.id).Meski sekarang sudah sangat jarang dan sulit ditemukan laporan terbaru tentang kasus skabies diberbagai media di Indonesia (terlepas dari faktor penyebabnya), namun tak dapat dipungkiri bahwa penyakit kulit ini masih merupakan salah satu penyakit yang sangat mengganggu aktivitas hidup dan kerja sehari-hari. Di berbagai belahan dunia, laporan kasus skabies masih sering ditemukan pada keadaan lingkungan yang padat penduduk, status ekonomi rendah, tingkat pendidikan yang rendah dan kualitas higienis pribadi yang kurang baik atau cenderung jelek. Rasa gatal yang ditimbulkannya terutama waktu malam hari, secara tidak langsung juga ikut mengganggu kelangsungan hidup masyarakat terutama tersitanya waktu untuk istirahat tidur, sehingga kegiatan yang akan dilakukannya disiang hari juga ikut terganggu. Jika hal ini dibiarkan berlangsung lama, maka efisiensi dan efektifitas kerja menjadi menurun yang akhirnya mengakibatkan menurunnya kualitas hidup masyarakat (http://www.litbang.depkes.go.id).Seperti yang telah disebutkan penyakit ini sering dijumpai pada tempat-tempat yang padat penduduknya dengan keadaan higiene yang buruk, termasuk salah satu tempat tersebut adalah di Pondok Pesantren. Terlepas dari semua keuntungan yang bisa diperoleh dari sebuah Pondok pesantren, tak lupa juga kita melihat beberapa kemungkinan buruk lain yang bisa terjadi dil ingkungan Pondok pesantren. Salah satunya adalah terkait dengan masalah kesehatan misalnya kejadian beberapa jenis penyakit kulit, hal ini dikarenakan keadaan asrama di pondok pesantren yang masih kurang memenuhi kriteria sehat, misalnya dalam satu kamar masih dihuni oleh banyak santri sehingga kemungkinan untuk tertular penyakit lebih besar, selain itu pula, perilaku hidup bersih dan sehat terutama hygiene perseorangan di pondok pesantren pada umumnya kurang mendapatkan perhatian dari santri. Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit yang salah satunya termasuk penyakit scabies. Kemungkinan ini juga karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para santri, tentang tanda dan gejala serta cara-cara penularan penyakit tersebut sehingga penanggulangan dan pencegahannyapun menjadi kurang maksimal (Badri, 2008 ).1.2. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya skabies di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat.1.3. Tujuan Penelitian1.3.a. Tujuan umum Untuk mengetahui Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya skabies di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri lombok Barat.1.3.b. Tujuan Khusus1. Untuk mengetahui kejadian skabies pada santri di Pondok Pesantren Nurul Hakim2. Untuk mengetahui faktor yang berperan terhadap terjadinya skabies.3. Untuk mengetahui faktor yang paling berperan terhadap terjadinya skabies dari semua faktor yang telah disebutkan.
1.4. Manfaat Penelitian1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan setempat agar lebih memperhatikan bahwasanya penderita skabies sebagian besar santri di pondok pesantren belum memahami tentang skabies.2. Merupakan bahan masukan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan dan strategi penanggulangan skabies oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan setempat serta pihak-pihak terkait lainnya.3. Merupakan laporan ilmiah untuk membantu memperkaya khasanah kepustakaan di bidang disiplin ilmu kesehatan pribadi, masyarakat dan lingkungan.4. Merupakan pengalaman berharga bagi penulis dalam upaya mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universtas Mataram serta menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman.5. Sebagai pengetahuan bagi santri-santri dan pengelola di pondok pesantren dalam upaya pencegahan dini terhadap skabies.
BAB 2TINJAUAN PUSTAKA
2. 1 . Definisi Skabies2. 1. 1. DefinisiSkabies atau penyakit kudis adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infestasi dan sensititasi terhadap Sarcoptes scabiei variates hominis ( Gandahusa, 2004 ). Pada tahun 1687, Benomo menemukan kutu skabies pada manusia dan VonHebra pada abad XIX telah melukiskan tentang pengetahuan dasar dari penyakit ini ( Harahap, 2000).2. 1. 2. Epidemiologi dan Faktor ResikoSkabies merupakan penyakit endemi pada banyak masyarakat. Penyakit ini dapat mengenai semua ras dan golongan di seluruh dunia. Penyakit ini banyak dijumpai pada anak dan orang dewasa muda, tetapi dapat juga mengenai semua umur. Insidensi sama pada pria dan wanita ( Harahap, 2000 ).Skabies ditemukan disemua negara dengan prevalensi yang bervariasi. Dibeberapa negara yang sedang berkembang prevalensi skabies sekitar 6 % - 27 % populasi umum dan cenderung tinggi pada anak-anak serta remaja. Ada dugaan bahwa setiap siklus 30 tahun terjadi epidemi skabies. Banyak faktor yang menunjang perkembangan penyakit ini, antara lain: sosial ekonomi yang rendah, higiene yang buruk, hubungan seksual yang sifatnya promiskuitas, kesalahan diagnosis, dan perkembangan dermografik serta ekologik. Penyakit ini dapat dimasukkan dalam PHS (Penyakit Hubungan Seksual) (http://www.litbang.depkes.go.id).Insidensi skabies di negara berkembang menunjukkan siklus fluktuasi yng sampai saat ini belum dapat dijelaskan. Interval antara akhir dari suatu epidemi dan permulaan epidemi berikutnya kurang lebih 10-15 tahun. Insidensinya di Indonesia masih cukup tinggi. Terendah di Sulawesi Utara dan tertinggi di Jawa Barat. Amiruddin dkk, dalam penelitian skabies di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya, menemukan insidensi penderita skabies selama tahun 1983-1984 adalah 2,7 %. Abu A juga dalam penelitiannya di Rumah Sakit Umum Dodi Ujung Pandang mendapat Insiden Skabies 0,67 % ( Harahap, 2000 ).Menurut Departemen Kesehatan RI prevalensi skabies di puskesmas selurauh Indonesia pada tahun 1986 adalah 4,6 % - 12,95 % dan skabies menduduki urutan ketiga dari 12 penyakit kulit tersering. Di bagian Kulit dan Kelamin FKUI/RSCM pada tahun 1988, dijumpai 704 kasus skabies yang merupakan 5,77 % dari seluruh kasus baru. Pada tahun 1989 dan 1990 prevalensi skabies adalah 6 % dan 3,9 % (http://www.litbang.depkes.go.id).2. 1. 3. EtiologiPenyakit ini disebabkan oleh Sarcoptes scabiei yang termasuk dalam filum Artropoda, kelas Arachnida, ordo Ackarima, famili Sarcoptes scabiei varites hominis. Selain itu juga terdapat sarcoptes scabiei yang lain, misalnya pada kambing dan babi (Djuanda, 2007 ).Ensiklopedi wikipedia (2009) juga memaparkan secara detail tentang klasifikasi spesifik tentang Sarcoptes scabiei yaitu : Kingdom: AnimaliPhylum: ArthropodaSubphylum: ChelicerataClass: ArachnidaSubclass: AcarinaSuperorde: AcariformesOrder: AstigmataSuborder: PsoroptidiaSuperfamily: SarcoptoideaFamily: Sarcoptidae2. 1. 4. Morfologi Gambar 1 : Sarcoptes scabiei pembesaran 10x10 Gambar 2 : Sacrcoptes scabiei(Atlas Parasitologi Kedokteran, 2004) (Parasitologi Kedokteran Edisi ketiga, 2004) Secara morfologik Sarcoptes scabiei merupakan tungau kecil, yang berbentuk oval, punggungnya cembung, dan bagian perutnya rata. Tungau ini translusen, berwarna putih kotor, dan tidak bermata. Ukurannya yang betina berkisar antara 330-450 mikron x 250-350 mikron, sedangkan yang jantan lebih kecil, yakni 200-240 mikron x 150-200 mikron. Bentuk dewasa mempunyai 4 pasang kaki, 2 pasang didepan sebagai alat untuk melekat dan 2 pasang kedua pada betina berakhir dengan rambut, sedangkan pada jantan pasangan kaki ketiga berakhir dengan rambut dan keempat berakhir dengan alat perekat (Djuanda, 2007).Badan Sarcoptes scabiei juga berupa kapitulum anterodorsal, yang mempunyai empat pasang kaki yang segmennya pendek. Untuk Sarcoptes scabiei yang jantan mempunyai pasangan kaki pertama dan kedua yang ambulakra berguna untuk melekat, pasangan kaki ketiga bulu cambuk, dan pasangan kaki keempat yang ambulakra. Sedangkan pada Sarcoptes scabiei yang betina mempunyai pasangan kaki pertama dan kedua yang ambulakra, pasangan kaki ketiga dan keempat ang berupa bulu cambuk (Priono, 2004).2. 1. 5. Siklus Hidup Untuk siklus hidupnya Sarcoptes scabiei adalah Setelah kopulasi (perkawinan ) yang terjadi diatas kulit, yang jantan akan mati, kadang-kadang masih dapat hidup beberapa hari dalam terowongan yang digali oleh yang betina. Tungau betina yang telah dibuahi menggali terowongan dalam stratum korneum, dengan kecepatan 2-3 milimeter sehari dan sambil meletakkan telurnya 2-4 butir sehari sampai mencapai 40 atau 50. bentuk betina yang dibuahi ini dapat hidup sebulan lamanya. Telur akan menetas, biasanya dalam waktu 3-5 hari, dan menjadi larva yang mempunyai 3 pasang kaki. Larva ini dapat tinggal dalam terowongan, tetapi dapat juga keluar. Setelah 2-3 hari larva akan menjadi nimfa yang mempunyai dua bentuk, jantan dan betina, dengan 4 pasang kaki. Seluruh siklus hidupnya dari telur sampai bentuk dewasa memerlukan waktu antara 8-12 hari (Djuanda, 2007 ).2. 1. 6. Patogenesis Tungau hidup didalam terowongan ditempat predileksi, yaitu jari tangan, pergelangan tangan bagian ventral, siku bagian luar, lipatan ketiak depan, umbilikus, daerah gluteus, ekstremitas, genital eksterna pada laki-laki dan areola mammae pada perempuan. Pada bayi dapat menyerang telapak tangan dan telapak kaki. Pada tempat predileksi dapat ditemukan terowongan berwarna putih abu-abu dengan panjang yang bervariasi, rata-rata 1mm, berbentuk lurus atau berkelok-kelok. Terowongan ini ditemukan bila belum terdapat infeksi sekunder. Diujung terowongan dapat ditemukan vesikel atau papul kecil. Terowongan yang berkelok-kelok umumnya ditemukan pada penderita kulit putih dan sangat jarang ditemukan pada penderita indonesia ( Gandahusa, 2004 ).2. 1. 7. Cara PenularanPenyakit scabies dapat ditularkan melalui kontak langsung maupun kontak tak langsung. Yang paling sering adalah kontak langsung dan erat atau dapat pula melalui alat-alat seperti tempat tidur, handuk, dan pakaian. Bahkan penyakit ini dapat pula ditularkan melalui hubungan seksual antara penderita dengan orang yang sehat. Di Amerika Serikat dilaporkan, bahwa scabies dapat ditularkan melalui hubungan seksual meskipun bukan merupakan akibat utama. Penyakit ini sangat erat kaitannya dengan kebersihan perseorangan dan lingkungan, atau apabila banyak orang yang tinggal secara bersama-sama disatu tempat yang relative sempit. Apabila tingkat kesadaran yang dimiliki oleh banyak kalangan masyarakat masih cukup rendah, derajat keterlibatan penduduk dalam melayani kebutuhan akan kesehatan yang masih kurang, kurangnya pemantauan kesehatan oleh pemerintah, faktor lingkungan terutama masalah penyediaan air bersih, serta kegagalanpelaksanaan program kesehatan yang masih sering kita jumpai, akan menambah panjang permasalahan kesehatan lingkungan yang telah ada (Anonim, 2009)Penularan skabies terjadi ketika orang-orang tidur bersama di satu tempat tidur yang sama di lingkungan rumah tangga, sekolah-sekolah yang menyediakan fasilitas asrama dan pemondokan, serta fasiltas-fasilitas kesehatan yang dipakai oleh masyarakat luas. Di Jerman terjadi peningkatan insidensi, sebagai akibat kontak langsung maupun tak langsung seperti tidur bersama. Faktor lainnya fasilitas umum yang dipakai secara bersama-sama di lingkungan padat penduduk. Dibeberapa sekolah didapatkan kasus pruritus selama beberapa bulan yang sebagian dari mereka telah mendapatkan pengobatan skabisid (Burkhart, 2008).
2. 1. 8. Gejala Klinik
Gambar 3 : Sarcoptes scabiei pada kulit dibagian pergelangan tangan (http://www.homeopathyandmore.com/med_images)
Gambar 4 : Regio dorsum manus dan palmar manus, papula tersebar disela-sela jari dan sepanjang pinggir jari. ( Atlas penyakit kulit dan kelamin, 2007 )Mansjoer (2000) memaparkan Gejala-gejala klinik dari skabies untuk membantu menegakkan diagnosia adalah dengan menemukan 2 dari 4 tanda kardinal berikut :1. Proritus nokturna ( gatal pada malam hari ) karena aktifitas tungau lebih tinggi pada suhu yang lebih lembab dan panas.2. Umumnya ditemukan pada sekelompok manusia, misalnya mengenai seluruh anggota keluarga.3. Adanya terowongan ( kunikulus ) pada tempat- tempat predileksi yang berwarna putih atau keabu-abuan, berbentuk garis lurus atau erkelok, rata-rata panjang 1cm, pada ujung terowongan itu ditemukan papul atau vesikel. Jika timbul infeksi sekunder ruam kulit menjadi polimorfi ( pustul, ekskoriasi, dll ). Tempat predileksi biasanya daerah dengan stratum korneum tipis, yaitu sela-sela jari-jari tangan, pergelangan tangan bagian volar, siku bagian luar, lipat ketiak bagian depan, areola mammae, dan lipat glutea, umbilikus, bokong, genitalia eksterna, dan perut bagian bawah4. Menemukan tungau merupakan hal yang paling diagnostik. Pada pasien yang selalu menjag higiene, lesi yang timbul ya sedikit sehingga diagnosis kadang kala sulit ditegakkan. Jika penyakit berlangsung lama, dapat timbul likenifikasi, impetigo, furunkulosis.2. 1. 9. Klasifikasi Terdapat beberapa bentuk skabies atipik yang jarang ditemukan dan sulit dikenal, sehingga dapat menimbulkan kesalahan diagnosis. Beberapa bentuk tersebut antara lain :1. Skabies pada orang bersih (scabies of cultivated). Bentuk ini ditandai dengan lesi berupa papul dan terowongan yang sedikit jumlahnya sehingga sangat sukar ditemukan. 2. Skabies incognito.Bentuk ini timbul pada scabies yang diobati dengan kortikosteroid sehingga gejala dan tanda klinis membaik, tetapi tungau tetap ada dan penularan masih bisa terjadi. Skabies incognito sering juga menunjukkan gejala klinis yang tidak biasa, distribusi atipik, lesi luas dan mirip penyakit lain. 3. Skabies nodularPada bentuk ini lesi berupa nodus coklat kemerahan yang gatal. Nodus biasanya terdapat didaerah tertutup, terutama pada genitalia laki-laki, inguinal dan aksila. Nodus ini timbul sebagai reaksi hipersensetivitas terhadap tungau scabies. Pada nodus yang berumur lebih dari satu bulan tungau jarang ditemukan. Nodus mungkin dapat menetap selama beberapa bulan sampai satu tahun meskipun telah diberi pengobatan anti scabies dan kortikosteroid.4. Skabies yang ditularkan melalui hewan.Di Amerika, sumber utama skabies adalah anjing. Kelainan ini berbeda dengan skabies manusia yaitu tidak terdapat terowongan, tidak menyerang sela jari dan genitalia eksterna. Lesi biasanya terdapat pada daerah dimana orang sering kontak/memeluk binatang kesayangannya yaitu paha, perut, dada dan lengan. Masa inkubasi lebih pendek dan transmisi lebih mudah. Kelainan ini bersifat sementara (4 8 minggu) dan dapat sembuh sendiri karena S. scabiei var. binatang tidak dapat melanjutkan siklus hidupnya pada manusia.5. Skabies Norwegia.Skabies Norwegia atau skabies krustosa ditandai oleh lesi yang luas dengan krusta, skuama generalisata dan hyperkeratosis yang tebal. Tempat predileksi biasanya kulit kepala yang berambut, telinga bokong, siku, lutut, telapak tangan dan kaki yang dapat disertai distrofi kuku. Berbeda dengan skabies biasa, rasa gatal pada penderita skabies Norwegia tidak menonjol tetapi bentuk ini sangat menular karena jumlah tungau yang menginfestasi sangat banyak (ribuan). Skabies Norwegia terjadi akibat defisiensi imunologik sehingga sistem imun tubuh gagal membatasi proliferasi tungau dapat berkembangbiak dengan mudah.
6. Skabies pada bayi dan anak.Lesi skabies pada anak dapat mengenai seluruh tubuh, termasuk seluruh kepala, leher, telapak tangan, telapak kaki, dan sering terjadi infeksi sekunder berupa impetigo, ektima sehingga terowongan jarang ditemukan. Pada bayi, lesi di muka.7. Skabies terbaring ditempat tidur (bed ridden).Penderita penyakit kronis dan orang tua yang terpaksa harus tinggal ditempat tidur dapat menderita skabies yang lesinya terbatas (Anonim, 2009)2. 1. 10. DiagnosisUntuk menegakkan diagnosis dapat dilakukan beberapa cara yaitu dengan melakukan anamnesis dan melihat gejala-gejala klinik yang khas dari penyakit ini. Sedangkan untuk mendapat diagnosis pasti dapat dilakukan pemeriksaan untuk menemukan tungau Sarcoptes scabiei dengan cara mencongkel atau mengeluarkan tungau dari kulit, kerokan kulit atau biopsi (Gandahusa, 2004 ).2. 1. 11. Diagnosis Banding Skabies merupakan the great immitater , karena menyerupai banyak penyakit kuli dengan keluhan gatal. Diagnosis bandingnya adalah prurigo, pedikulosis korporis, dermatitis, dan lain sebagainya. Setiap dermatitis yang mengenai daerah areola, selain penyakit paget harus dicurigai pula adanya skabies. Skabies krustosa dapat menyerupai drmatitis hiperkeratosis, psoriasis, dan dermatitis kontak ( Harahap, 2000 ).2. 1. 12. Pemeriksaan Penunjang Seperti yang telah disebutkan bahwa untuk mendapat diagnosis pasti dari penyakit skabies ini maka pemeriksa harus bisa menemukan tungau Sarcoptes scabiei maka dari itu dapat dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang untuk menemukan tungau tersebut. Pemeriksaan penunjang tersebut antara lain :a. Pertama mencari terowongan, kemudian pada ujung dapat terlihat papul atau vesikel. Mencongkel dengan jarum dan diletakkan diatas kaca objek, lalu tutup dengan kaca penutup dan lihat dengan mikroskop cahaya.b. Dengan cara menyikat dengan sikat dan ditampung diatas selembar kertas putih dan dilihat dengan kaca pembesar.c. Dengan membuat biopsi irisan. Caranya : jepit lesi dengan 2 jari kemudian bua irisan tipis dengan pisau dan periksa dengan mikroskop cahaya.d. Dengan biopsi eksisional dan periksa dengan pewarnaan HE. (Mansjoer, 2000 ).2. 1. 13. PengobatanSyarat obat yang ideal untuk mengobati penyakit kulit skabies ini adalah efektif terhadap semua stadium tungau, tidak menimbulkan iritasi dan tidak toksik, tidak berbau atau kotor, tidak merusak atau mewarnai pakaian, mudah diperoleh, dan harganya murah. Dan obat yang banyak digunakan untuk skabies ini adalah jenis obat topikal yaitu :a. Belerang endap (sulfur presipitatum ) 4-20 % dalam bentuk salep atau krm. Pada bayi dan orang dewasa sulfur presipitatum 5 % dalam minyak sangat aman dan efektif. Kekurangannya adalah pemakaian tidak boleh kurang dari 3 hari karena tidak efektif terhadap stadium telur, berbau, mengotpri pakaian, dan dapat menimbulkan iritasi.b. Emulsi benzil-benzoat 20-25 % efektif terhadap semua stadium, diberikan setiap malam selama 3 kali. Obat ini sulit diperoleh, sering memberi iritasi, dan kadang-kadang makin gatal setelah dipakai.c. Gama benzena heksaklorida ( gameksan ) 1% dalam bentuk krim atau losio, termasuk obat pilihan karena efektif terhadap semua statium, mudah digunakan, dan jarang memberi iritasi. Obat ini tidak dianjurkan pada anak dibawah 6 tahun dan wanita hamil karena toksik terhadap susunan saraf pusat. Pemberiannya cukup sekali selama 8 jam. Jika masih ada gejala, di ulangi seminggu kemudian.d. Krotamiton 10 % dalam krim atau losio mempunyai dua efek sebagai antiskabies dan antigatal. Harus dijauhkan dari mata, mulut, dan uretra. Digunakan selama 2 malam berturut-turut dan dibersihkan setelah 24 jam pemakaian terakhir.e. Krim permetrin 5 % merupakan obat yang paling efektif dan aman karena sangat mematikan untuk parasit S. Scabiei dan memiliki toksisitas rendah terhadap manusia (Mansjoer (2000) dan Meinking (1995) ).Gambar 5 . Evaluasi Infeksi Skabies ( http://en.wikipedia.org )
Infeksi hari ke 4Infeksi hari ke 8 mulai pengobatanInfeksi hari ke 12, dalam pengobatanSembuh dan sehat
2. 1. 14. KomplikasiBila skabies tidak diobati selama beberapa minggu atau bulan, dapat timbul dermatits akibat garukan. Erupsi dapat berbentuk impetigo, ektima, selulitis, limfangitis, folikulitis, dan furunkel. Dermatitis iritan dapat timbul kerana penggunaan preparat antiskabies yang berlebihan, baik pada terapi awal atau dari pemakaian yang terlalu sering. Salep sulfur, dengan konentrasi 15 % dapat menyebabkan dermatitis bila digunakan terus-menerus selama beberapa hari pada kulit yang ipis. Benzilbenzoat juga dapat menyebabkan iritasi bila digunakan 2x sehari dalam beberapa hari ( Harahap, 2000 ).
2. 1. 15. Prognosis Dengan memperhatikan pemilihan obat dan cara pemakaian obat, syarat pengobatan, dan menghilangkan faktor predisposisi, penyakit ini dapat diberantas dan memberi prognosis yang lebih baik (Mansjoer, 2000).2. 1. 16. Pencegahan Tidak ada vaksin yang tersedia untuk skabies, juga tidak terbukti ada faktor-faktor risiko yang bermakna dalam menyebabkan terjadinya skabies, Oleh karena itu, pencegahan secara umum adalah fokus pada strategi untuk mencegah infeksi ulang. Semua keluarga dan orang yang dekat harus ditangani pada saat yang sama dengan penderita skabies, meskipun belum memperlihatkan adanya gejala yang sama. Pembersihan lingkungan harus terjadi secara simultan, Untuk mengurangi resiko terkena infeksi. Karena keadaan lingkungan yang kurang sehat dapat memudahkan penyebaran penyakit ini. Untuk itu dianjurkan untuk sering mencuci beberapa perlengkapan dengan menggunakan air panas seperti pakaian, seprai, dan handuk yang telah kontak dengan tungau penyebab skabies. Dalam membersihkan lingkungan harus mencakup: a. Membersihkan Ranjang dan kasur. b. Membersihkan debu yang ada di lantai, dan karpet.c. Mengepel permukaan lantai dan kamar mandi.d. Membersihkan shower dan bak mandi setelah digunakan.e. Menyetrika semua pakaian, handuk dan seprai sebelum digunakan (Herman, 2001).
2. 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi2. 2. 1. LingkunganLingkungan adalah suatu sistem kompleks yang berada diluar individu yang memepengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Setiap organisme, hidup dalam ligkungannyanya masing-masing. Faktor-faktor yang ada dalam lingkungan selain berinteraksi dengan organisme, juga berinteraksi sesama faktor tersebut, sehingga sulit untuk memisahkan dan mengubahnya tanpa mempengaruhi bagian dari lingkungan itu. Lingkungan merupakan ruang tiga dimensi, di dalam mana organisme merupakan salah satu bagiannya.Interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu proses yang wajar dan terlaksana sejak manusia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena manusia memerlukan daya dukung unsur-unsur lingkunga untuk kelangsungan hidupnya. Udara, air. Makanan, sandang, papan, dan seluruh kebutuhan manusia harus diambil dari lingkungan hidupnya. Akan tetapi dalam proses interaksi manusia dengan lingkungannya ini tidak selalu didapatkan keuntungan, kadang-kadang manusia mendapat kerugian. Misalnya, seorang makan dan minum untuk menghilangkan lapar dan dahaga, tetapi ia dapat menjadi sakit karenanya. Jumlah makanan dan minuman yang terlalu banyak maupun terlalu sedikit dapat menimbulkan kelainan nutrisi. Begitu juga apabila makanan ataupun minuman yang mengandung zat-zat berbahaya bagi kesehatan, berupa racun asli yang berasal dari makanan ataupun akibat kontaminasi dengan mikroba patogen atau zat kimia yang berbahaya, sehingga dapat terjadi keracunan atau penyakit. Hal ini merupakan hubungan timbal balik antara aktivitas manusia dengan lingkungannya ( Slamet, 2004 ).Sanitasi merupakan salah satu komponen dari kesehatan lingkungan, yaitu perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup bersih untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Dalam penerapannya di masyarakat, sanitasi meliputi penyediaan air, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, kontrol vektor, pencegahan dan pengontrolan pencemaran tanah, sanitasi makanan, serta pencemaran udara. ( Djamal, 2003 ).Kesehatan manusia tidak lepas dari pengaruh lingkungan; makin ideal lingkungan akan makin baik pula manusia yang hidup di dalamnya. Meskipun demikian tidak semua zat yang ada di lingkungan mendukung kehidupan atau status kesehatan seseorang, beberapa di antaranya apalagi jika kadarnya berlebihan dapat membahayakan. (http. www.kalbe.co.id/cdk)2. 2. 2. SikapSikap atau yang dalam bahasa inggris disebut attitude adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang. Suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan cara tertentu terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Dalam beberapa hal, sikap merupakan penentu yang sangat penting dalam tingkah laku manusia. Sebagai reaksi, maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang (like) atau tidak senang (dislike), menurut dan melaksanakannya atau menjauhi/menghindari sesuatu (Purwanto, 2007).Setiap orang mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap suatu perangsang. Ini disebabkan oleh berbagai faktor yang ada pada individu masing-masing seperti adanya perbedaan dalam bakat, minat, pengalaman, pengetahuan, intensitas perasaan, dan juga situasi lingkungan. Pengetahuan yang dimiliki seseorang sangat mempengaruhi sikap dan tindakannya (Purwanto, 2007).2. 2. 3. PerilakuPerilaku adalah tindakan atau perbuatan organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Perilaku tidak sama dengan sikap. Sikap hanyalah sebagian dari perilaku manusia. Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behaviour). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbuatan yang nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas, disamping itu juga diperlukan faktor dukungan (support) dari pihak lain.Tingkat-tingkat praktek :1. Persepsi (Perception)Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil adalah merupakan praktek tingkat pertama. Misalnya seorang ibu dapat memilih makanan yang bergizi tinggi bagi anak balitanya.2. Respon Terpimpin (Guided Respons)Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar sesuai dengan contoh adalah merupakan indikator praktek tingkat dua. Misalnya : seorang ibu dapat memasak sayur dengan benar, mulai dari cara mencuci dan memotong-motongnya, lamanya memasak, menutup pancinya, dan sebagainya.3. Mekanisme (Mechanism)Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan maka ia sudah mencapai praktek tingkat tiga. Misalnya seorang ibu yang sudah biasa mengimunisasikan bayi pada umur-umur tertentu, tanpa menunggu perintah atau ajakan orang lain4. Adaptasi (Adaptation)Adaptasi adalah suatu praktek atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya tindakan itu sudah dimodifikasi sendiri tanpa mengurangi kebenaran tindakannya tersebut. Misalnya ibu dapat memilih dan memasak makanan yang bergizi tinggi berdasarkan bahan-bahan yang murah dan sederhana (Notoatmodjo, 2003).2. 2. 4. PengetahuanPengetahuan adalah berasal dari kata tahu dan ini terjadi setelah melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindera dan sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 1993).Menurut Notoatmodjo (1993), pengetahuan yang mencakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan yaitu:1. Tahu (know)Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkatan ini adalah mengingat kembali terhadap suatu yang spesifik dan keseluruhan bahan yang dipelajari atau rangsangan yang diterima.2. Memahami (comprehension)Diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan obyek yang diketahui dan menginterpretasikan materi tersebut secara benar.3. Aplikasi (Aplication)Sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi sebenarnya.4. Analisa (analysis)Analisa adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu obyek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.
5. Sintesis (syntesis)Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru, atau dengan kata lain sistesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada.6. Evaluasi (evaluation)Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi obyek. Penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria yang telah ada.Menurut Haditono (1994), faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah sebagai berikut:1. PendidikanPendidikan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat pengtahuan seseorang. Makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi.2. UsiaDalam kehidupan masyarakat, peranan seseorang ditentukan oleh usianya. Anak kecil dan remaja tidak memiliki peranan yang penting di dalam suatu lingkungan masyarakat, melainkan usia seseorang yang sudah dalam kategori usia dewasa. Hal ini didasarkan pada anggapan masyarakat bahwa usia dewasa akan mempunyai pikiran dan solusi yang lebih baik dan masuk akal daripada seseorang dengan usia yang lebih muda. Ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, sebagian besar peranan masyarakat didominasi oleh usia dewasa (Sarwono, 1999). Semakin tua, semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpai dan semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga semakin menambah pengetahuannya. Dikatakan juga semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat, seseorang yang lebih dewasa akan lebih dipercaya dari orang yang belum dewasa. Hal ini sebagai akibat pengalaman dan kematangan jiwanya (Haditono, 1994).3. Pengalaman Selain usia, faktor lain yang menyebabkan perbedaan pengetahuan antara responden yang memilki pendidikan yang sama yaitu perbedaan pengalaman. (Haditono, 1994).Aspek pengetahuan seseorang terkait dengan pengembangan kognitif. Ciri khasnya terletak pada kemampuan orang memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk representasi yang mewakili obyek-obyek yang dihadapi, apakah obyek tersebut berupa orang, benda, atau kejadian/peristiwa. Obyek-obyek tersebut direpresentasikan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang-lambang yang semuanya merupakan sesuatu yang bersifat mental. Selanjutnya, gagasan dan tanggapan itu dituangkan dalam kata-kata yang disampaikan kepada orang yang mendengarkan. Pengetahuan juga ditentukan oleh kemampuan berbahasa seseorang, dimana bahasa tersebut digunakan untuk mengungkapkan gagasan dan pikirannya. Semakin baik kemampuan berbahasa untuk mengungkapkan gagasan dan pikiran tersebut, maka semakin baik kemampuannya menggunakan potensi kognitif secara efisien dan efektif. Kemampuan berbahasa pun harus dikembangkan melalui belajar dan dapat membentuk tingkat pengetahuan seseorang mengenai segala sesuatu dalam lingkungannya (Wingkel, 1991).
3. 3. Definisi Santri Santri merupakan unsur yang penting sekali dalam perkembangan sebuah pesantren karena langkah pertama dalam tahap-tahap membangun pesantren adalah bahwa harus ada murid yang datang untuk belajar dari seorang alim. Kalau murid itu sudah menetap di rumah seorang alim, baru seorang alim itu bisa disebut kyai dan mulai membangun fasilitas yang lebih lengkap untuk pondoknya (Madjid, 2009 ). Santri biasanya terdiri dari dua kelompok, yaitu santri kalong dan santri mukim. Santri kalong merupakan bagian santri yang tidak menetap dalam pondok tetapi pulang ke rumah masing-masing sesudah selesai mengikuti suatu pelajaran di pesantren. Santri kalong biasanya berasal dari daerah-daerah sekitar pesantren jadi tidak keberatan kalau sering pergi pulang. Makna santri mukim ialah putera atau puteri yang menetap dalam pondok pesantren dan biasanya berasal dari daerah jauh. Pada masa lalu, kesempatan untuk pergi dan menetap di sebuah pesantren yang jauh merupakan suatu keistimewaan untuk santri karena dia harus penuh cita-cita, memiliki keberanian yang cukup dan siap menghadapi sendiri tantangan yang akan dialaminya di pesantren (Walsh, 2002). Salah satu aspek kehidupan sehari-hari para santri adalah ketidakperluannya untuk diawasi atau dikelola oleh para guru atau Pak Kyai. Tentu saja kadang terjadi kasus spesifik di mana Pak Kyai perlu ikut campur, tetapi pada umumnya kedisiplinan para santri di sangat tinggi sehingga sehingga setiap santri tidak perlu diperintah untuk mengerjakan sesuatu yang seharusnya dia sudah kerjakan. Bahwasanya, ada dua alasan bagi para santri untuk mengelola sendiri kegiatan sehari-harinya. Pertama, peraturan-peraturan pondok dan jadwal sehari-hari yang sangat ketat yang berarti santri cuma tinggal ikut kegiatan-kegiatan yang dimasukkan jadwal untuk hari tertentu. Maka tidak susah untuk dikelola (Anonim, 2009).
2. 4. Definisi Pondok Pesantren Definisi singkat istilah pondok adalah tempat sederhana yang merupakan tempat tinggal kyai bersama para santrinya. Di Jawa, besarnya pondok tergantung pada jumlah santrinya. Adanya pondok yang sangat kecil dengan jumlah santri kurang dari seratus sampai pondok yang memiliki tanah yang luas dengan jumlah santri lebih dari tiga ribu. Tanpa memperhatikan berapa jumlah santri, asrama santri wanita selalu dipisahkan dengan asrama santri laki-laki (Walsh, 2002 ).Pondok Pesantren adalah salah satu pendidikan islam di indonesia yang mempunyai ciri khas tersendiri. Definisi pesantren sendiri mempunyai pengertian yang bervariasi, tetapi pada hakekatnya mengandung pengertian yang sama. Perkataan Pesantren berasal dari bahasa sansekerta yang memperoleh wujud dan pengertian tersendiri dalam bahasa indonesia. Asal kata san berarti orang baik ( laki-laki ) disambung tra berarti suka menolong. Pesantren berarti tempat untuk membina manusia menjadi orang baik (Madjid, 2009). Secara umum pondok pesantren memiliki beberapa komponen yaitu, seorang kiai yang merupakan suatu hal yang mutlak bagi sebuah pesantren, sebab dia adalah tokoh sentral yang memberikan pengajaran juga karena kiai menjadi salah satu unsur yang paling dominan dalam kehidupan suatu pesantren. Kemudian santri yang merupakan unsur pokok dari suatu pesantren biasanya terdiri dari dua kelompok yaitu santri yang menetap dalam pesantren dan santri yang hanya belajar tetapi tidak menetap dalam pesantren. Selanjutnya terdapat pondok yang merupakan tempat tinggal kiai dan para santrinya dan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan belajar mengajar. Unsur lain yang cukup membedakan pesantren dengan lembaga lainnya adalah bahwa pada pesantren diajarkan kitab-kitab islam klasik yang sekarang terkenal dengan sebutan kitab kuning (Walsh, 2002).Komplek sebuah pesantren memiliki gedung-gedung selain dari asrama santri dan rumah kyai, termasuk perumahan ustad, gedung madrasah, lapangan olahraga, kantin, koperasi, lahan pertanian dan/atau lahan pertenakan. Kadang-kadang bangunan pondok didirikan sendiri oleh kyai dan kadang-kadang oleh penduduk desa yang bekerja sama untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan. Salah satu niat pondok selain dari yang dimaksudkan sebagai tempat asrama para santri adalah sebagai tempat latihan bagi santri untuk mengembangkan ketrampilan kemandiriannya agar mereka siap hidup mandiri dalam masyarakat sesudah tamat dari pesantren. Santri harus memasak sendiri, mencuci pakaian sendiri dan diberi tugas seperti memelihara lingkungan pondok (Anonim, 2009).Pendidikan pesantren merupakan pendidikan tertua di Indonesia, hingga saat ini model pendidikan pesantren masih bertahan di tengah-tengah modernisasi pendidikan diluar pesantren itu sendiri. Kemampuan pesantren dalam mengembangkan diri dan masyarakat sekitarnya dikarenakan adanya potensi yang dinilai oleh pondok pesantren itu sendiri misalnya karena Pondok pesantren hidup selama 24 jam, dengan pola 24 jam tersebut, ponok pesantren baik sebagai lembaga pendidikan keagamaan, sosial masyarakat, atau sebagai lembaga pengembangan potensi umat dapat diterapkan secara tuntas, optimal, dan terpadu, sehingga kecenrdungan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren memang didasari oleh kepercayaan mereka terhadap pembinaan yang dilakukan oleh pondok pesantren terhadap pendidikan agama bisa lebih maksimal (http://ibda.files.wordpress.com).
BAB 3METODOLOGI PENELITI
3. 1. Desain PenelitianDilihat dari cara analisa datanya, maka jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian Deskriptif karena pada penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mendiskripsikan faktor- faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya skabies pada santri itu sendiri. Pada penelitian ini akan mendeskripsikan dan memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi dengan melakukan analisa terlebih dahulu terhadap data-data yang sudah dikumpulkan.Kemudian jika dilihat dari waktu penelitiannnya, maka penelitian ini termasuk studi Cross sectional karena dalam mempelajari hubungan antara variabel-variabel yang termasuk dalam tingkat pengetahuan dengan variabel efek ( terjadinya penyakit skabies ) diobservasi sekaligus pada waktu yang sama.3.2. Tempat dan Waktu Penelitian ini akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat. Waktu penelitian adalah dari bulan Juni 2010 Februari 2011. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut :NoUraianJuniJuliAgustusSeptemberNopemberDesemberJanuariFebruari
1.Penyusunan Proposal dan konsultasiXXX
2.Perlengkapan Administrasi dan PerizinanX
3.Uji KuesionerX
4.Pengumpulan DataX
5.Pengolahan DataXX
6.Penulisan LaporanXX
3.3. Populasi dan Sampel3. 3. I Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santri yang pernah dan sedang menderita skabies berdasarkan data kunjungan santri ke klinik Ibnu Sina di Pondok Pesantren Nurul Hakim dari tahun 2008-2010. Adapun jumlah pada tahun 2008 sebanyak 69 orang, tahun 2009 sebanyak 74 orang, tahun 2010 sebanyak 95 orang, jadi jumlah seluruhnya 238 orang.3. 3. I Sampel1. Perkiraan Jumlah SampelKarena jumlah populasi lebih kecil dari 10.000 maka besar sampel dihitung menggunakan rumus ( Notoatmodjo,2002 ):
n = n = 70, 4 peneliti membulatkan menjadi 70 Keterangan : N = Besar populasi n = Besar sampel d = Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan, peneliti menggunakan 0,1. Jadi besar sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 70 orang.2. Teknik SamplingTeknik pengambilan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel secara acak sistemis ( Systematic sampling ). Teknik ini merupakan modifikasi dari sampel random sampling. caranya adalah, membagi jumlah atau anggota populasi dengan perkiraan jumlah sampel yang diinginkan. Hasilnya adalah interval sampel. Pada penelitian ini interval sampelnya adalah 238 : 70 = 3,4 dibulatkan menjadi 3. Maka anggota populasi yang terkena sampel adalah setiap orang yang mempunyai nomor kelipatan 3, yakni 3, 6, 9, 12, dan seterusnya sampai mencapai jumlah 70 anggota sampel.( Notoatmodjo, 2002 ).3.4. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 3.4.1. Kriteria Inklusi Yang termasuk kriteria inklusi adalah :a. Tercatat sebagai santri dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat.b. Santri/Santriwati pernah atau saat ini sedang menderita penyakit kulit skabiesc. Santri/ Santriwati hadir pada saat penelitian dilakukand. Santri/ Santriwati tersebut bersedia mengisi kuesioner yang diberikan. 3.4.2.Kriteria Eksklusi Kriteria Eksklusi adalah semua yang tidak termasuk dalan kriteria Inklusi diatas.3.5. Definisi Operasionala. Pengetahuan tentang penyakit skabies adalah segala sesuatu yang diketahui responden dalam usaha pencegahan dan pengobatan penyakit skabies. Meliputi pengertian penyakit skabies, cara penularan baik langsung maupun tidak langsung, masa inkubasi kuman skabies, gejala-gejala penyakit skabies, daerah yang paling sering terkena, dan cara-cara pencegahan agar tidak tertular. Untuk tingkat pengetahuan dikelompokkan menjadi tiga kategori dengan metode skoring (Nursalam, 2003) yaitu :1. Pengetahuan Baik : mampu menjawab benar pertanyaan 81-100%2. Pengetahuan Cukup : mampu menjawab benar pertanyaan 61-80%3. Pengetahuan Kurang : mampu menjawab benar pertanyaan < 60%b. Sikap tentang skabies adalah pandangan, pendapat responden dalam upaya pencegahan penyakit skabies di pondok pesantren meliputi sikap responden tentang pentingnya kebersihan diri, sikap responden memutus cara penularan baik langsung maupun tidak langsung dengan meminjamkan pakaian, perlengkapan tidur kepada teman, dan sikap responden agar tidak tertular. Untuk sikap menggunakan dua kriteria ( Andayani, 2005 ) yaitu:1. Sikap Positif2. Sikap Negatifc. Perilaku tentang skabies adalah tindakan santri dalam usaha pencegahan penyakit skabies. ( Andayani, 2005 )d. Lingkungan yang berkaitan dengan skabies adalah keadaan disekitar tempat tinggal santri yang dapat mempengaruhi terjadinya skabies. Lingkungan tersebut meliputi sanitasi gedung, sanitasi kamar mandi, sanitasi hunian kamar, dan ketersediaan air bersih. Untuk menggambarkan keadaan lingkungan menggunakan dua kriteria ( Marufi, 2005 ) yaitu ;1. Lingkungan Baik 2. Lingkungan Buruke. Skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infestasi dan sensitisasi terhadap Sarcoptes scabiei varietas hominis dan produknya. (Djuanda et al, 2007).
3.6. Cara Kerja Langkah langkah kerja yang dilaksanakan pada penelitian ini meliputi :1. Menyusun proposal2. Melengkapi kebutuhan Administrasi, Ethical Clearence, dan Uji contoh Kuesioner.3. Mengumpulkan data yang diperoleh dengan memberikan kuesioner pada santri untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya skabies.4. Mengolah data yang diperoleh.5. Menganalisa data yang diperoleh dengan sistem SPSS
3.7. Identifikasi Variabel 3. 7. 1. Variabel BebasYang merupakan Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan santri tentang skabies dan sikap serta perilaku para santri dalam kesehariannya di Pondok Pesantren tersebut. 3. 7. 2. Variabel Tergantung Variabel tergantung adalah kejadian skabies pada santri 3.8. Instrumen dan Prosedur Penelitian Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data. Santri yang menjadi responden dalam penelitian ini masing-masing diberikan kuesioner yang akan diisi, dengan sebelumnya diberikan pengarahan dan petunjuk mengenai cara pengisian kuesioner tersebut. Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang bersifat tertutup. Pada kuesioner ini terdiri dari terdiri dari lima bagian pertanyaan yaitu pengantar, karakteristik responden, pengetahuan, sikap, keadaan lingkungan. Pada kuesioner ini akan dilakukan uji validitas dan uji reabilitas pada beberapa santri lain yang tidak termasuk sampel lain, hal ini disebabkan karena sampel yang pernah digunakan sebagai uji validitas tidak boleh digunakan lagi menjadi sampel untuk penelitian. 3.9. Manajemen dan Analisis DataMetode analisa yang akan digunakan adalah analisis deskriptif berupa nilai rerata yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik santri yaitu tingkat pengetahuan terhadap skabies. Tingkat pengetahuan responden dijabarkan sesuai dengan pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Data hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel. Pengolahan data responden dapat diuraikan sebagai berikut:1. Pengolahan data tingkat pengetahuan responden terhadap skabies diolah secara deskriptif dan dikelompokkan menjadi tiga kategori dengan metode skoring. ( Nursalam, 2003 ) yaitu :1. Pengetahuan Baik : mampu menjawab benar pertanyaan 81-100%.2. Pengetahuan Cukup : mampu menjawab benar pertanyaan 61-80%3. Pengetahuan Kurang : mampu menjawab benar pertanyaan < 60% 2. Skala sikap (attitude scales) berupa kumpulan pernyataan-pernyataan mengenai suatu objek sikap (Saifuddin, 2003). Data sikap responden terhadap penyakit skabies diolah secara deskriptif dan dikategorikan menjadi dua yaitu positif dan negatif dengan perhitungan skor menggunakan rumus:
T = 50 + 10 Keterangan: x: Skor Responden
: Nilai rata-rata responden (mean) SD: Standar Deviasi Sikap dikatakan positif bila skor : T > 50 Sikap dikatakan negatif bila skor : T < 503.Pengolahan data mengenai keadaan lingkungan yang terkait dengan beberapa parameter yang dapat mempengaruhi terjadinya skabies adalah dengan menggunkan dua kriteria (Marufi, 2005 ) yaitu : 1. Keadaan Lingkungan Baik : menjawab ya 50 % 2. Keadaan Lingkungan Buruk : menjawab ya < 50% Keterangan : pilihan jawaban ya menggambarkan keadaan lingkungan yang buruk. 3. 10 Analisis dataMetode analisis yang akan digunakan adalah analisis deskriptif berupa nilai rerata yang digunakan untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan prilaku santri tentang penyakit skabies. Sikap responden dijabarkan sesuai dengan pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Data hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisa dengan uji statistik menggunakan uji Chi-Square dengan bantuan SPSS 15.0
BAB 4HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Uji Instrumen PenelitianPenelitian ini diawali dengan uji instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuoesioner. Uji kuesioner ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur. Reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap hal yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama.Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu ukuran atau nilai menunjukkan tingkat kehandalan atau kesahihan suatu alat ukur dengan cara mengukur korelasi antara variabel atau item dengan sskor total variabel. Jika nilai r hitung > r tabel. Maka dinyatakan valid, sedangkan jika r hitung < r tabel, maka dinyatakan tidak valid. Dalam penelitian ini, uji validitas kuesioner dilakukan pada 20 orang responden yang memiliki kriteria yang sama dengan sampel penelitian.Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari variabel pengetahuan, sikap, dan lingkungan. Variabel pengetahuan terdiri atas 16 pertanyaan, hasil pengujian variabel pengetahuan didapatkan hasil r hitung untuk 16 pertanyaan masing-masing 0,451; 0,464; 0,468; 0,525; 0,504; 0,496; 0,468; 0,531, 0,497; 0,553; 0,675; 0,468; 0,482; 0,470; 0,717; 0,610 dan r tabelnya yaitu 0,423.. Variabel sikap terdiri atas 10 pertanyaan, hasil pengujian variabel sikap didapatkan hasil r hitung untuk 10 pertanyaan masing-masing 0,447; 0,587; 0,443; 0,468; 0,771; 0,508; 0,508; 0,714; 0,529; 0,518 dan r tabelnya yaitu 0,423. Variabel lingkungan terdiri atas 10 pertanyaan, hasil pengujian variabel lingkungan didapatkan hasil r hitung untuk 10 pertanyaan masing-masing 0,456; 0,530; 0,530; 0,474; 0,432; 0,441; 0,485; 0,530; 0,485; 0,594 dan r tabelnya yaitu 0,423. Dari data tersebut terlihat bahwa r hitung > r tabel. Sehingga dapt dikatakan bahwa kuesioner untuk variabel pengetahuan, sikap, dan lingkungan dinyatakan valid.4.2 Hasil Penelitian4.2.1 Karakteristik Responden Tabel 4. 1 Distribusi Responden Berdasarkan UsiaNoKelompok Usia (tahun)FrekuensiPersentase (%)
112-133042,9
214-152130,0
3>151927,1
Jumlah70100
Berdasarkan tabel 4. 1 , responden terbanyak berasal dari kelompok usia 12-13 tahun yaitu 30 orang ( 42,9% ), selanjutnya diikuti oleh kelompok usia 14-15 tahun yaitu 21 orang ( 30% ), dan yang terakhir adalah kelompok usia > 15 tahun yaitu sebanyak 19 orang ( 27,1%). Tabel 4. 2 Distribusi Responden Bedasarkan Jenis KelaminNoJenis KelaminFrekuensiPersentase (%)
1L3550
2P3550
Jumlah70100
Berdasarkan tabel 4. 2, distribusi responden berdasarkan jenis kelamin adalah untuk jenis kelamin laki-laki terdapat 35 orang ( 50% ) dan untuk jenis kelamin perempuan juga terdapat 35 orang ( 50% ).
4.2.2 Penyebaran Responden Berdasarkan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya SkabiesTabel 4.3 Penyebaran Responden Berdasarkan Pengetahuan yang Mempengaruhi Terjadinya SkabiesNoPengetahuanFrekuensiPersentase (%)
1Baik34,3
2Cukup2941,4
3Kurang3854,3
Jumlah70100
Berdasarkan tabel 4. 3, responden yang mempunyai pengetahuan yang baik adalah sebanyak 3 orang ( 4,3% ), sedang yang mempunyai pengetahuan yang cukup adalah sebanyak 29 orang ( 41,4% ), dan yang mempunyai pengetahuan yang kurang adalah sebanyak 38 orang ( 54,3% ).Tabel 4. 4 Penyebaran Responden Berdasarkan Sikap yang Mempengaruhi Terjadinya SkabiesNoSikapFrekuensiPersentase (%)
1Positif4158,6
2Negatif2941,4
Jumlah70100
Berdasarkan tabel 4. 4 , responden yang mempunyai sikap yang positif adalah sebanyak 41 orang ( 58,6% ), sedangkan responden yang mempunyai sikap yang negatif adalah 29 orang ( 41,4% ).
Tabel 4. 5 Penyebaran Responden Berdasarkan Lingkungan yang Mempengaruhi Terjadinya SkabiesNoLingkunganFrekuensiPersentase (%)
1Baik2434,3
2Buruk4665,7
Jumlah70100
Berdasarkan tabel 4.5 , responden yang tinggal pada lingkungan yang baik adalah sebanyak 24 orang ( 34,3% ) dan responden yang tinggal pada lingkungan yang buruk adalah sebanyak 46 orang ( 65,7% ).
4.2.3 Penyebaran Responden Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Terhadap Pengetahuan, Sikap, dan Lingkungan yang Memepengaruhi Terjadinya Skabies
Tabel 4. 6 Peyebaran Responden Berdasarkan Umur Terhadap PengetahuanNoUmur(tahun)PengetahuanTotal
BaikCukupKurang
n%n%n%n%
112-130071023333043
214-151112178112130
3>152310147101927
Total342941385470100
Berdasarkan tabel 4.6 , responden pada kelompok usia 12-13 tahun yang mempunyai pengetahuan yang baik adalah 0, pengetahuan yang cukup sebanyak 7 orang ( 10% ), dan pengetahuan yang kurang adalah sebanyak 23 orang ( 33% ). Untuk kelompok usia 14-15 tahun dengan pengetahuan yang baik adalah 1 orang ( 1% ), pengetahuan yang cukup sebanyak 12 orang ( 17% ), dan pengetahuan yang kurang adalah sebanyak 8 orang ( 11% ). Dan untuk kelompok usia >15 tahun dengan pengetahuan yang baik adalah sebanyak 2 orang ( 3% ), pengetahuan yang cukup sebanyak 10 orang ( 14% ), dan pengetahuan yang kurang sebanyak 7 orang ( 10% ).Tabel 4. 7 Penyebaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Terhadap PengetahuanNoJenis KelaminPengetahuanTotal
BaikCukupKurang
n%n%n%n%
1L11162318283550
2P23131920293550
Total342942385470100
Berdasarkan tabel 4. 7, responden yang berjenis kelamin laki-laki dengan pengetahuan yang baik yaitu 1 orang ( 1% ), dengan pengetahuan yang cukup sebanyak 16 orang ( 23% ), dan dengan pengetahuan yang kurang sebanyak 18 orang ( 28% ). Untuk responden yang berjenis kelamin wanita, yang mempunyai pengetahuan yang baik yaitu sebanyak 2 orang ( 3% ), dengan pengetahuan yang cukup sbanyak 13 orang ( 19% ), dan dengan pengetahuan yang kurang sebanyak 20 orang ( 29% ).
Tabel 4. 8 Penyebaran Responden Berdasarkan Umur Terhadap SikapNoUmur(tahun)SikapTotal
PositifNegatif
n%n%n%
112-13142015212941
214-151623692232
3>1511168111927
Total4159294170100
Berdasarkan tabel 4. 8, responden dengan kelompok umur 12- 13 tahun yang mempunyai sikap yang positif yaitu sebanyak 14 orang ( 20% ), dan yang mempunyai sikap negatif sebanyak 15 orang ( 21% ). Untuk kelompok umur 14-15 tahun yang mempunyai sikap positif yaitu sebanyak 16 orang ( 16% ) dan sikap yang negatif sebanyak 6 orang ( 9% ). Untuk kelompok umur > 15 tahun, responden yang mempunyai sikap positif sebanyak 11 orang ( 16% ) dan dengan sikap negatif sebanyak 8 orang ( 11% ).Tabel 4. 9 Penyebaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Terhadap SikapNoJenis KelaminSikapTotal
PositifNegatif
n%n%n%
1L142021303550
2P27398113550
Total4159294170100
Berdasarkan tabel 4.9, responden yang berjenis kelamin laki-laki yang mempunyai sikap yang positif yaitu 14 orang ( 20% ), dan yang mempunyai sikap negatif sebanyak 21 orang ( 30% ). Untuk responden yang berjenis kelamin wanita, yang mempunyai sikap yang positif yaitu sebanyak 27 orang ( 39% ), dan yang mempunyai sikap yang negatif sebanyak 8 orang ( 11% ). Tabel. 4. 10 Penyebaran Responden Berdasarkan Umur Terhadap LingkunganNoUmur(tahun)LingkunganTotal
BaikBuruk
n%n%n%
112-13202910143043
214-151724462130
3>1591310141927
Total4666243470100
Berdasarkan tabel 4. 10, responden dengan kelompok umur 12- 13 tahun yang tinggal pada lingkungan yang baik yaitu sebanyak 20 orang ( 20% ), dan yang tinggal pada lingkungan yang buruk sebanyak 10 orang ( 14% ). Untuk kelompok umur 14-15 tahun yang tinggal pada lingkungan yang baik yaitu sebanyak 17 orang ( 24% ) dan yang tinggal pada lingkungan yang buruk sebanyak 4 orang ( 6% ). Untuk kelompok umur > 15 tahun, responden yang tinggal pada lingkungan yang baik sebanyak 9 orang ( 13% ) dan yang tinggal pada lingkungan yang buruk sebanyak 10 orang (14%).
Tabel 4. 11 Penyebaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Terhadap LingkunganNoJenis KelaminLingkunganTotal
Baik Buruk
n%n%n%
1L121723333550
2P121723333550
Total2434466670100
Berdasarkan tabel 4.11, responden yang berjenis kelamin laki-laki yang tinggal pada lingkungan yang baik yaitu sebanyak 12 orang ( 17% ), dan yang tinggal pada lingkungan yang buruk sebanyak 23 orang ( 33% ). Untuk responden yang berjenis kelamin wanita, yang tinggal pada lingkungan yang baik yaitu sebanyak 12 orang ( 17% ), dan yang tinggal pada lingkungan yang buruk sebanyak 23 orang ( 33% ).
4.2.4 Analisis DataTabel 4.12 Hubungan Antara Umur dan Jenis kelamin Responden Dengan Pengetahuan Responden yang mempengaruhi terjadinya Skabies.VariabelKategoriPengetahuanUji KemaknaanpKeterangan
BaikCukupKurang
Umur12-130723Chi-square0,017Bermakna
14-151128
>152107
Jenis KelaminL11618Chi-square0,688Tidak bemakna
P21320
Berdasarkan tabel 4.12, dengan uji kemaknaan chi-square dan tingkat kepercayaan 95%, terlihat bahwa terdapat hubungan bermakna antara umur responden dengan tingakat pengetahuannya terhadap skabies, sedangkan untuk jenis kelamin didaptkan hubungan yang tidak bermakna terhadap tingkat pengetahuan responden.
Tabel 4.13 Hubungan Antara Umur dan Jenis kelamin Responden Dengan Sikap Responden yang mempengaruhi terjadinya Skabies
VariabelKategoriSikapUji KemaknaanpKeterangan
PositifNegatif
Umur12-131515Chi-square0,310
Tidak Bermakna
14-15156
>15118
Jenis KelaminL1421Chi-square0,002Bermakna
P278
Berdasarkan tabel 4.13, dengan uji kemaknaan chi-square dan tingkat kepercayaan 95%, terlihat bahwa terdapat hubungan bermakna antara jenis kelamin responden dengan sikap yang dilakukan , sedangkan untuk umur didapatkan hubungan yang tidak bermakna terhadap sikap responden.
Tabel 4. 14 Hubungan Antara Umur dan Jenis kelamin Responden Dengan Lingkungan Responden yang mempengaruhi terjadinya Skabies
VariabelKategoriLingkunganUji KemaknaanpKeterangan
BaikBuruk
Umur12-131020Chi-square0,085Tidak bermakna
14-15417
>151019
Jenis KelaminL1223Chi-square1.000Tidak Bermakna
P1223
Berdasarkan tabel 4.14, dengan uji kemaknaan chi-square dan tingkat kepercayaan 95%, terlihat bahwa terdapat hubungan tidak bermakna baik antara umur responden dengan lingkungan maupun antara jenis kelamin responden dengan keadaan lingkungan yang ada.Tabel 4.15 Perbandingan Besar Nilai Kemaknaan Antara Pengetahuan, Sikap, dan Lingkungan Terhadap Kejadian Sabies.
NoFaktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Skabiesp.valueUji KemaknaanKeterangan
1Pengetahuan0,000Chi-SquareBermakna
2Sikap0,151Chi-SquareTidak bermakna
3Lingkungan0,009Chi-SquareBermakna
Berdasarkan tabel 4.15, dengan ui kemaknaan chi-square dan tingkat kepercayaan 95% terlihat bahwa terdapat perbandingan yang bermkana antara pengetahuan dan lingkungan terhadap terjadinya Skabies. Perbandingan yang tidak bermakna ditemukan pada sikap santri terhadap terjadinya skabies.
4.3 PembahasanHasil yang diperoleh dari penelitian ini, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan santri tentang skabies masih kurang yaitu 54,3% sedangkan reponden dengan tingkat pengetahuan cukup dan baik, masing-masing 41,4% dan 4,3%. Hasil yang berbeda didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh Apris Hartanti di Pondok Pesantren Darul Abror Pasar Batang Brebes, dimana dalam penelitian tersebut responden yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik adalah 43,1% ( Hartanti, 2007).Tingkat pengetahuan responden yang masih kurang terhadap skabies ini dapat disebabkan karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh santri tersebut dari tenaga kesehatan ataupun dari para pendidik dan pembina yang berada di Pondok Pesantren tersebut, seperti salah satu contoh adalah tidak pernah diadakan penyuluhan tentang penyakit skabies , padahal telah kita ketahui bahwa penyakit skabies ini mempunyai resiko tinggi terjadi pada keadaan dimana terdapat cara hidup berkelompok seperti pada Pondok Pesantren.Untuk meningkatkan derajat kesehatan santri perlu adanya upaya untuk meningkatkan pengetahuan santri tentang kesehatan secara umum, khususnya tentang penyakit menular sehingga diharapkan ada perubahan sikap serta diikuti dengan perubahan prilaku kebersihan perorangan dengan hasil akhir menurunnya angka kesakitan penyakit menular. Upaya peningkatan, pencegahan dan penanggulangan masalah penyakit menular dapat ditempatkan sebagai ujung tombak paradigma sehat untuk mencapai Indonesia sehat 2010 (Herryanto, 2004).Pengetahuan tentang skabies yang termasuk dalam tiga terbanyak tidak diketahui oleh santri di Pondok Pesantren Nurul Hakim adalah mengenai penyebab dari penyakit skabies ( 82,8%), cara penularan skabies ( 70% ), ciri khas dari penyakit skabies (61,4%). Sebagian besar santri menjawab bahwa penyakit skabies tersebut disebabkan oleh alergi, dan mereka menganggap penyakit skabies tersebut sama dengan penyakit kulit lainnya, bahkan mereka mengira penyakit skabies menular hanya melalui kontak langsung saja.Dari hasil penelitian terdapat 3 santri ( 4,3 % ) yang mempunyai tingkat pengetahuan tinggi dan menderita skabies. Hal ini menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi terjadinya skabies, meskipun pengetahuannya baik, jika keadaan lingkungannya masih dalam kategori kurang baik atau bersih, maka kemungkinan untuk menderita penyakit skabies itu tetap ada, sikap santri juga bisa mempengaruhi, meskipun mereka mengetahui tetapi masih ada beberapa sikaps yang tidak bisa dirubah misalnya menumpuk kasur setelah mereka bangun tidur, karena itu sudah menjadi peraturan di Pondok Pesantren itu sendiri.Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang adalah usia ( Haditono, 1994 ). Teori ini sesuai dengan hasil peneliatian yang didapat. Pada penelitian ini didapatkan bahwa responden pada kelompok usia 12-13 tahun tidak ada responden yang mempunyai tingkat pengetahuan yang baik, pada kelompok usia 14 15 tahun terdapat 1 responden ( 1% ) dengan tingkat pengetahuan yang baik, sedangkan responden pada kelompok usia > 15 tahun terdapat 2 ( 3% ) responden dengan tingkat pengetahuan baik. Berdasarkan tabel 4. 12 juga dapat dilihat dari hasil uji kemaknaan terdapat hubungan yang bermakna antara usia dengan tingkat pengetahuan responden. Sedangkan untuk jenis kelamin tidak ada hubungan yang bermakna dengan tingkat pengetahuan. Hal ini disebabkan karena tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam mencari pengetahuan.Berdasarkan tabel 4.4 didapatkan bahwa responden yang mempunyai sikap positif adalah 41 orang ( 58,6% ) dan responden dengan sikap negatif adalah 29 orang ( 41,4% ). Hal ini sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Apris Hartanti di Pondok Pesantren Darul Abror Pasar Batang Brebes, dimana dalam penelitian tersebut responden dengan sikap buruk atau negatif sedikit lebih tinggi yaitu sebanyak 55,4% ( Hartanti, 2007).Sikap negatif yang masih banyak dilakukan oleh para santri adalah mengenai kebiasaan mereka yang tidak pernah menyetrika pakaian, handuk, dan seprai sebelum digunakan ( 78,5%), kebiasaan santri yang tidak mengganti seprai sekali seminggu ( 74,2% ), dan kebiasaan santri menggunakan satu pakaian lebih dari satu hari ( 71,4% ). Meski sekarang para santri selalu mandi menggunakan sabun, dan sudah jarang bertukar pakaian dengan temannya, namun sikap negatif yang lain masih ada, jadi kemungkinan untuk terkena penyakit skabies juga masih ada.Status kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sikap dan perilaku seseorang dalam merespon suatu penyakit, skabies pada umumnya merupakan jenis penyakit menular. Sikap santri sangat penting peranannya dalam pencegahan skabies di lingkungan Asrama Pondok yang membutuhkan kebersihan perorangan serta perilaku yang sehat. Sikap yang dimiliki oleh santri diharapkan dapat berpengaruh terhadap perilaku mereka guna mencegah terjadinya skabies di lingkungan Pondok tempat mereka tinggal. Tidur bersama, pakaian kotor yang digantung atau ditumpuk di kamar merupakan contoh lain dari sikap negatif yang dapat menimbulkan skabies ( Nugraheni, 2008 ).Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sikap adalah pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayan, media massa, lembaga pendidikan dan faktor emosional ( Azwar, 2005 ). Hal ini dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan pada santri di Pondok pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, dimana sikap masing- masing santi masih dipengaruhi oleh orang lain. Sikap juga dapat dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang ( Purwanto, 2007 ). Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian bahwa responden yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik atau cukup cenderung mempunyai sikap yang positif. Namun Pengetahuan yang cukup baik mengenai kebersihan perorangan tidaklah berarti bila tidak menghasilkan respon bathin dalam bentuk sikap, sikap merupakan hal yang paling penting . Sikap dapat digunakan untuk memprediksikan tingkah laku apa yang mungkin terjadi, dengan demikian sikap dapat diartikan sebagai suatu predisposisi tingkah laku yang akan tampak aktual apabila kesempatan untuk mengatakan terbuka luas (Azwar, 2005).Dapat dilihat pada hasil penelitian pada tabel 4.9 , bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak yang memiliki sikap posotif ( 39% ) dibanding responden yang berjenis kelamin laki-laki ( 20% ). Untuk sikap yang negatif juga dapat dilihat perbedaannya pada responden perempuan terdapat ( 11% ) dan pada laki-laki terdapat ( 30%). Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jenis kelamin dapat mempengaruhi sikap, hal ini juga dapat dilihat pada tabel 4.13, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan sikap dari responden. Sedangkan untuk umur tidak didapatkan hubungan yang bermakna terhadap sikap.Para santri dapat menghindari atau mencegah terjadinya penyakit skabies dengan menjaga kebersihan dirinya, contoh sederhana adalah selalu mandi menggunakan sabun, sebagai salah satu alternatif pengobatan bagi santri yang terkena penyakit skabies adalah dengan mandi menggunakan sabun yang mengandung sabun sulfur atau belerang karena kandungan pada sulfur bersifat antiseptik dan antiparasit, tetapi pemakaian sabun sulfur tidak boleh berlebihan karena membuat kulit menjadi kering ( Sadana,2007 ). Selain menjaga kebersihan diri perlu juga menjaga kebersihan pakaiannya dengan rajin mencuci dan menjemur pakaian sampai kering dibawah terik matahari. Dan jangan menggunakan pakaian yang belum kering atau lembab. Biasakan mencuci sedikit tapi sering. Selain pakaian kebersihan perlengkapan lain juga perlu untuk diperhatikan, misalnya handuk dan seprai yang digunakan, disarankan bagi para santri untuk sering mencuci handuk dan seprai serta menyetrika sebelum digunakan.Selain pengetahuan dan sikap, lingkungan juga mempunyai peran penting dalam mempengaruhi terjadinya skabies, pada penelitian didapatkan bahwa responden yang berada pada lingkungan yang baik adalah 24 orang ( 34,3% ) dan responden yang tinggal pada lingkungan yang buruk adalah 46 orang ( 65,7% ). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soedjajadi Keman dkk pada santri di Pondok Pesantren Kabupaten Lamongan. Pada penelitian tersebut Soedjajadi Keman dkk membahas keadaan lingkungan pesantren yang buruk meliputi parameter sanitasi gedung, sanitasi kamar mandi, dan kepadatan hunian gedung, hasil yang didapatkan adalah dari 245 orang yang tinggal pada lingkungan yang buruk tersebut 71, 40% yang menderita skabies dan pada responden yang tinggal pada lingkungan yang baik hanya 45, 20 % yang menderita skabies ( Keman, 2003 )Penularan penyakit skabies terjadi bila kebersihan pribadi dan kebersihan lingkungan tidak terjaga dengan baik. Faktanya, sebagian pesantren tumbuh dalam lingkungan yang kumuh, tempat mandi dan WC yang kotor, lingkungan yang lembab, dan sanitasi buruk (Badri, 2008).Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa santri tinggal diruangan yang luasnya 6m x 6m dengan jumlah penghuni 15-18 orang, bisa dihitung masing-masing santri mendapat jatah ruangan seluas 2- 2,4 m2 , padahal seperti yang telah disebutkan oleh Notoatmodjo (2003) bahwa Luas bangunan yang optimum adalah apabila menyediakan 2,5-3 m2 untuk tiap orang. Jadi, bisa dibayangkan bagaimana kehidupan mereka dalam satu ruangan tersebut. Pada saat tidur, jarak santri satu dengan yang lain cukup dekat, hal inilah yang menyebabkan penularan penyakit melalui kontak langsung menjadi lebih mudah. Meskipun ventilasi memenuhi syarat untuk pencahayaan, tetapi keadaan kamar yang masih tidak mendukung menyebabkan bakteri penyebab skabies masih bisa hidup, keadaan tersebut misalnya menumpuk kasur setelah digunakan, terdapat pakaian-pakaian yang masih digantung didalam kamar. Jadi salah satu usaha untuk mencegah terjadi penularan penyakit skabies ini adalah dengan sering menjemur kasur, karena bakteri penyebab skabies akan mati dengan panas matahari. Bakteri penyebab skabies ini dapat bertahan hidup pada suhu kamar selama 2-3 hari dan aktivitasnya tinggi pada kelembaban 40-80 % ( http://www.docstoc.com/docs/4794542/Scabies ).Selain keadaan fisik bangunan, sanitasi lingkungan yang meliputi penyediaan air bersih juga sangat berpengaruh. Penyediaan air bersih merupakan kunci utama sanitasi kamar mandi yang berperan terhadap penularan penyakit Skabies pada santri Pondok pesantren, karena penyakit skabies merupakan penyakit yang berbasis pada persyaratan air bersih ( water washed disease ) yang dipergunakan untuk membasuh anggota badan sewaktu mandi ( Azwar, 1995 ). Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/menkes/sk/xi/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan industri terdapat pengertian mengenai air bersih yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak.Kebutuhan manusia akan air sangat kompleks antara lain untuk minum, masak, mandi, mencuci ( bermacam-macam cucian ) dan sebagainya. Menurut perhitungan WHO di negara- negara maju tiap orang memerlukan air antara 60-120 liter perhari. Sedangkan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia tiap orang memerlukan air antara 30-60 liter perhari (Notoatmodjo, 2003 )Di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, sumber air bersih yang digunakan santri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berasal dari sumber air sumur dan PDAM. Namun ketersediaan air selalu berubah setiap waktu, kadang tersedia air yang cukup banyak, kadang kala juga PDAM macet dan ketersediaan air menjadi terbatas, diperkirakan jika tidak ada gangguan sumber air maka setiap santri bisa menggunakan lebih kurang 40-50 liter perorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi jika terdapat gangguan pada sumber air maka setiap santri hanya mempunyai jatah 20-30 liter air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Untuk kamar mandi, masih ada beberapa kamar mandi yang terdiri atas beberapa sekat ruangan akan tetapi bak yang digunakan untuk menampung air menjadi satu, dapat simpulkan transmisi penyakit kulit yang menular, seperti skabies dapat terjadi dengan mudah. Kebutuhan air bersih yang masih kurang bagi para santri untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari juga menjadi penyebab. Ketersediaan air yang kurang terkadang menyebabkan santri hanya mandi satu kali sehari, dan untuk mencuci juga tidak bisa langsung mencuci pakaian yg sudah kotor, jadi para santri akan menumpuk pakaian kotor mereka.Keadaan lingkungan seperti itu tidak akan bisa dirubah oleh pihak pengelolah pesantren dalam waktu singkat, butuh waktu untuk kembali mengatur sanitasi tersebut, namun beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan lebih dahulu adalah menjaga sumber air agar ketersediaan air bersih bisa mencukupi semua kebutuhan santri. Salah satu cara misalnya menyediakan bak penampungan air yang besar dan dijaga kebersihannyas, sehingga pada saat ketersediaan air melimpah, bisa ditampung terlebih dahulu dan digunakan kemudian jika ketersediaan air berkurang karena adanya gangguan dari sumber air. Untuk perbaikan bentuk kamar mandi , mungkin bisa dilakukan secara bertahap.Departemen Kesehatan RI ( 1996 ) telah menyebutkan salah satu kegiatan untuk menangani masalah sanitasi lingkungan adalah adalah perbaikan kualitas air di tempat pendidikan agama atau Pondok Pesantren. Ada tiga kegiatan pokok yang harus dilakukan yaitu berupa pengawasan kualitas air, perbaikan kualitas air, dan pembinaan pemakaian air. Ketiga kegiatan pokok tersebut merupakan suatu rangakaian kegiatan yang dilakukan secara utuh dalam suatu lokasi tempat pendidikan agama atau Pondok Pesantren.Keadaan lingkungan pesantren tidak bisa dihubungkan dengan usia dan jenis kelamin seperti halnya tingkat pengetahuan dan sikap dari responden. Hal ini disebabkan karena lingkungan pesantren dari uji kemaknaan pada hasil penelitian di tabel 4.15, didapatkan tidak ada hubungan yang bermakna baik antara umur dengan keadaan lingkungan maupun jenis kelamin pada lingkungan.Santri dan santriwati yang tinggal di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat ini tinggal pada keadaan yang sama dari semua usia dan jenis kelamin, sama-sama tinggal di ruangan yang luasnya sama dan didalamnya tinggal lebih dari sepuluh orang bahkan ada yang tinggal sampai 18 orang. Hal ini seperti disampaikan oleh Notoatmodjo ( 2007 ) tentang luas lantai bangunan, yaitu luas lantai bangunan rumah atau tempat tinggal yang sehat harus cukup untuk penghuni didalamnya, artinya luas lantai bangunan tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya. Luas bangunan yang tidak sebanding dengan penghuninya akan menyebabkan sesak. Hal ini tidak sehat, sebab disamping menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen, juga bila salah satu penghuni terkena penyakit infeksi, akan mudah menular kepada anggota penghuni yang lain. Dari hasil penelitian yang didapatkan, dari 70 responden, 83% responden mengaku bahwa terdapat santri lain yang menderita penyakit skabies dikamarnya.Memang keadaan lingkungan tersebut tidak bisa dirubah secara signifikan, tetapi mungkin bisa sedikit dikendalikan agar bisa menjadi keadaan yang lebih baik. Banyak faktor yang menjadi penyebab menurunnya kualitas lingkungan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan, sehingga mereka kurang respon untuk dapat menerima informasi yang bermanfaat bagi dirinya. Untuk meningkatkan mutu lingkungan, pendidikan mempunyai peranan penting, karena melalui pendidikan, manusia semakin mengetahui dan sadar akan bahaya dari lingkungan yang buruk, terutama bahaya pencemaran terhadap kesehatan manusia ( Koesnadi, 2000 ). Selain itu sosial ekonomi dan sosial budaya juga bisa mempengaruhi.Penyakit skabies ini tidak bisa hanya disebabkan oleh satu faktor saja, banyak faktor yang dapat mempengaruhi, dan antara faktor yang satu dengan faktor yang lain saling berhubunga. Dari ketiga faktor yang telah disebutkan, berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.15 dengan uji kemaknaa Chi-square didapatkan nilai p untuk pengetahuan kurang < 0,05 (0,000) artinya faktor pengetahuan ini bermakna dalam menyebabkan terjadinya skabies, nilai p untuk sikap > 0,05 ( 0,151 ) artinya faktor sikap tidak bermakna terhadap terjadinya skabies. Nilai p untuk faktor lingkungan < 0,05 ( 0,009 ) ini berarti faktor lingkungan bermakna terhadap terjadinya skabies. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disamping lingkungan, pengetahuan merupakan faktor yang paling berperan terhadap terjadinya skabies pada santri di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat.
BAB 5KESIMPULAN DAN SARAN
5. 1 Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan dapat disimpulkan bahwa :1. Sebanyak 38 responden ( 54,3% ) mempunyai tingkat pengetahuan yang masih kurang terhadap skabies, responden dengan tingkat pengetahuan yang baik dan cukup masing-masing sebanyak 3 responden ( 4,3 % ) dan 29 responden ( 41,4% ).2. Pengetahuan tentang skabies yang termasuk tiga terbanyak yang tidak diketahui oleh responden adalah mengenai penyebab penyakit ( 82,8% ), cara penularan penyakit ( 70 % ), dan ciri khas dari penyakit skabies ( 61,4% ).3. Sikap positif dimiliki oleh 41 responden ( 58,6% ) dan responden yang memiliki sikap negatif sebanyak 29 orang ( 41,4% ).4. Sikap negatif yang masih banyak dilakukan para responden adalah mengenai kebiasaan mereka yang tidak pernah menyetrika pakaian, handuk, dan seprai sebelum digunakan ( 78,5% ), kebiasaan santri yang tidak mengganti seprai sekali seminggu ( 72,2% ), dan kebiasaan santri menggunakan satu pakaian lebih dari satu hari ( 71,4% ).5. Keadaan lingkungan pesantren masih tergolong buruk, meskipun kualitas fisik air sudah baik tetapi ketersediaannya masih terbatas dan kepadatan hunian kamar tidur masih tinggi.6. Terdapat hubungan bermakna antara umur dengan pengetahuan ( p = 0,017 ), dan hubungan bermakna antara jenis kelamin dengan sikap ( p = 0,002 )7. Faktor yang berperan terhadap terjadinya skabies adalah pengetahuan dan lingkungan dengan hasil uji kemaknaan masing-masing pengetahuan ( p= 0,000 ) dan lingkungan ( p = 0,009 ).
5. 2 Saran1. Untuk menambah tingkat pengetahuan santri tentang skabies diharapkan kepada pembina Pondok Pesantren untuk memberikan informasi yang lebih banyak pada santri, mungkin dengan adanya kerja sama dengan tenaga kesehatan yang terkait.2. Disarankan bagi setiap santri agar lebih memperhatikan personal hygine, salah satu caranya dengan menjaga kebersihan badan dan perlengkapan kebutuhan lainnya.3. Bagi Pengelola Pondok Pesantren untuk lebih memperhatikan keadaan lingkungan pesantren terutama tentang ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kepadatan hunian setiap kamar santri. Harus sesuai dengan standar kesehatan yang sudah ditentukan.
3
27
2.5 Kerangka Konsep
PengetahuanSikapKeterampilan PerilakuSantri Sehat LingkunganSantri dengan skabiesSosialBiologisFisikKeterangan : : Diteliti : Tidak ditelitiSarcoptes scabiei