Review Perbandingan Paradigma
-
Upload
r-yogie-prawira-w -
Category
Documents
-
view
60 -
download
1
Transcript of Review Perbandingan Paradigma
Menurut Guba (1990), paradigma merupakan serangkaian keyakinan dasar yang membimbing tindakan. Paradigma berurusan dengan prinsip-prinsip pertama, atau prinsip-prinsip dasar. Suatu paradigma meliputi tiga elemen: epistemologi, ontologi, dan metodologi. Epistemologi mengajukan pertanyaan, bagaimana kita mengetahui dunia? Hubungan apa yang muncul antara peneliti dengan yang diketahui? Ontologi memunculkan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang hakikat realitas. Metodologi memfokuskan diri pada cara kita meraih pengetahuan tentang dunia.Konstruktivisme, seperti yang dipaparkan oleh Guba dan Lincoln, mengadopsi ontologi kaum relativis (ontologi relativisme), epistemologi transaksional, dan metodologi hermeutis dan dialektis. Tujuan-tujuan penelitian dari paradigma ini diarahkan untuk menghasilkan berbagai pemahaman yang bersifat rekonstruksi, yang di dalamnya kriteria kaum positivis tradisional tentang validitas internal dan eksternal digantikan dengan terma-terma sifat layak dipercaya (trustworthiness) dan otentisitas (authenticity).Thomas Schwandt menganalisis pendekatan konstruktivis dan interpretivis mengidentifikasi perbedaan dan aliran pemikiran utama yang ada dalam kedua pendekatan ini, yang dipersatukan oleh penentangan keduanya terhadap positivisme, dan komitmennya untuk mempelajari dunia dari sudut pandang individu yang berinteraksi. Kedua perspektif ini diyakini oleh Schwandt, lebih dibedakan oleh komitmennya pada soal-soal tentang cara mengetahui (epistemologi) dan wujud (ontologi), daripada oleh metodologi spesifiknya, yang pada dasarnya menegakkan pendekatan emik dan idiografik terhadap penelitian. Tradisi kaum konstruktivis, seperti yang ditengarai oleh Schwandt, merupakan tradisi yang kaya, mendalam, dan kompleks.Bidang keilmuan yang sama rumitnya juga menguraikan teori kritis yang bermacam-macam dan model-model kaum Marxis yang saat ini menyebar luas dalam berbagai wacana penelitian kualitatif. Menurut Guba dan Lincoln, paradigma ini, dalam berbagai macam bentuknya, menegaskan sebuah ontologi yang didasarkan pada realisme historis, sebuah epistemologi yang bersifat transaksional, dan sebuah metodologi yang bersifat dialogis dan dialektis. Joe Kincheloe dan Peter McLaren menguraikan secara singkat beberapa cara dimana penelitian yang berbasis teori kritis dapat mendorong ke arah pemberdayaan pekerja. Para ahli teori kritis mencoba menghasilkan berbagai transformasi dalam tatanan sosial dengan menghasilkan ilmu pengetahuan yang berciri historis dan struktural, yang dinilai menurut tingkat keterposisian sejarahnya dan kemampuannya untuk menghasilkan praktis, atau tindakan.Kepercayaan Dasar (Metafisika) dari Paradigma Penelitian Kritis dan KonstruktivismeItem Teori KritisKonstruktivisme
OntologiRealisme historis realitas maya yang dibentuk oleh nilai-nilai sosial, politik, ekonomi, etnik dan gender, mengkristal seiring perjalanan waktuRelativisme realitas yang dikonstruksikan secara lokal dan spesifik
EpistemologiTransaksional/subjektivis; temuan-temuan yang diperantarai oleh nilaiTransaksional/subjektivis; temuan-temuan yang diciptakan
Metodologi Dialog/dialektisHermeneutis/dialektis
Teori Kritis dan Posisi Ideologi TerkaitOntologi: Realisme Historis. Sebuah realitas dianggap bisa dipahami pernah suatu ketika berciri lentur, namun, dari waktu ke waktu, dibentuk oleh serangkaian faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnik dan gender, yang kemudian mengkristal (membatu) ke dalam serangkaian struktur yang saat ini (secara tidak tepat) dipandang sebagai yang nyata, yakni alamiah dan abadi. Demi tujuan-tujuan praktis, struktur tersebut adalah nyata, yakni sebuah realitas maya atau historis.Epistemologi: Transaksional dan Subjektivis. Peneliti dan objek yang diteliti terhubung secara interaktif, dengan nilai-nilai peneliti (dan nilai orang-orang lain yang terposisikan) memengaruhi penelitian secara tak terhindarkan. Oleh karenanya, temuan-temuan penelitian diperantarai oleh nilai. Sesuatu yang dapat diketahui terjalin secara erat dengan interaksi antara seorang peneliti tertentu dengan objek atau kelompok tertentu.Metodologi: Dialogis dan Dialektis. Sifat transaksional penelitian membutuhkan dialog antara peneliti dengan subjek-subjek penelitian; dialog tersebut haruslah berciri dialektis agar dapat mengubah ketidaktahuan dan kesalahpahaman (yakni, menerima struktur-struktur yang diperantarai secara historis sebagai yang tak dapat diubah) menjadi kesadaran yang lebih mendalam/matang (yang menyadari bagaimana struktur-struktur dapat diubah dan memahami tindakan apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan), atau sebagai intelektual informatif guna menyingkap dan menggali bentuk-bentuk pengetahuan historis dan terkungkung yang mengacu pada pengalaman akan penderitaan, konflik, dan perjuangan kolektif; untuk mengaitkan gagasan tentang pemahaman historis dengan elemen-elemen kritik dan harapan.KonstruktivismeOntologi: Relativis. Realitas bisa dipahami dalam bentuk konstruksi mental yang bermacam-macam dan tak dapat diindra, yang didasarkan secara sosial dan pengalaman, berciri lokal spesifik (meskipun berbagai elemen sering kali bersama-sama dimiliki oleh berbagai individu dan bahkan bersifat lintas budaya), dan bentuk serta isinya bergantung pada manusia atau kelompok individual yang memiliki konstruksi tersebut. Konstruksi (mental) tersebut tidak kurang atau lebih benar, dalam pengertian mutlak, namun sekadar lebih matang dan/atau canggih. Konstruksi tersebut dapat diubah, sebagaimana realitas ikutannya juga demikian.Epistemologi: Transaksional dan Subjektivis. Peneliti dan objek penelitian dianggap terhubung secara timbal balik sehingga hasil-hasil penelitian terciptakan secara literal seiring dengan berjalannya proses penelitian. Pembedaan konvensional antara ontologi dan epistemologi pun lenyap, sebagaimana yang terjadi dalam teori kritis.Metodologi: Hermeneutis dan Dialektis. Sifat variabel dan personal (intramental) dari konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermeneutik konvensional dan dikomparasikan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi konsensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk konstruksi etika peneliti).
Posisi Paradigma dalam Masalah-Masalah Praktis PilihanMasalah Teori KritisKonstruktivisme
Tujuan penelitianKritik dan transformasi; pemulihan dan emansipasiPemahaman; rekonstruksi
Sifat ilmu pengetahuanWawasan struktural/historisBerbagai rekonstruksi individual bersatu membentuk konsensus
Akumulasi pengetahuanRevisionisme historis; generalisasi melalui similaritasRekonstruksi yang lebih matang dan canggih; pengalaman yang seolah dialami sendiri
Kriteria baik-buruknya atau kualitasKeterposisian historis; lenyapnya ketidaktahuan stimulus tindakanLayak dipercaya dan keontetikan serta kesalahpahaman
Nilai Tercakup berciri formatif
Etika Intrinsik; kecondongan moral ke arah ilhamIntrinsik; proses yang condong ke arah penyingkapan rahasia; persoalan-persoalan khusus
Suara intelektual transformatif sebagai pembela dan aktivispartisipan yang penuh empati dan gairah sebagai fasilitator bagi rekonstruksi multi-pesan
Pelatihan Sosialisasi ulang; kualitatif dan kuantitatif; sejarah; nilai-nilai altruisme dan pemberdayaan
Akomodasi Tidak sepadan
Hegemoni Mencari pengakuan dan masukan
Dalam teori kritis, tujuan penelitian adalah kritik dan transformasi struktur sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan gender yang mengekang serta menindas umat manusia, melalui keterlibatan dalam upaya perlawanan, bahkan konflik. Kriteria kemajuannya adalah bahwa pemulihan dan emansipasi sebaiknya terjadi dan terus berlangsung sepanjang waktu. Advokasi dan aktivisme merupakan konsep utama. Peneliti terposisikan dalam peran pendorong dan fasilitator, yang menyiratkan bahwa peneliti secara a priori memahami apa saja transformasi yang diperlukan. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penilaian tentang transformasi apa yang diperlukan harus dikhususkan bagi orang-orang yang hidupnya paling terpengaruh oleh transformasi, yakni para partisipan penelitian itu sendiri.Sementara itu, tujuan penelitian dengan paradigma konstruktivisme adalah untuk memahami dan merekonstruksi berbagai kosntruksi yang sebelumnya dipegang orang (termasuk peneliti), yang berusaha ke arah konsensus, namun masih terbuka bagi interpretasi baru seiring dengan perkembangan informasi dan kecanggihan. Kriteria kemajuannya adalah bahwa seiring dengan perjalanan waktu, setiap orang akan merumuskan konstruksi yang lebih matang dan canggih dan semakin menyadari isi dan makna dari berbagai konstruksi yang bersaing. Advokasi dan aktivisme juga merupakan konsep utama dalam pandangan ini. Dalam proses ini peneliti akan terposisikan dalam peran partisipan dan fasilitator; sebuah posisi yang dikritik oleh sejumlah kritikus berdasarkan alasan bahwa posisi tersebut melebarkan peran peneliti hingga melampaui batas-batas rasional keahlian dan kompetensinya.Sifat ilmu pengetahuan. Dalam teori kritis, pengetahuan terdiri atas sekumpulan wawasan struktural/historis yang hendak ditransformasikan seiring berjalannya waktu. Transformasi terjadi ketika ketidaktahuan dan kesalahpahaman memunculkan pemahaman/wawasan yang lebih matang melalui interaksi dialektis. Sementara itu, dalam pandangan paradigma konstruktivisme, pengetahuan terdiri atas berbagai konstruksi yang memiliki konsensus relatif (atau sekurang-kurangnya gerakan tertentu menuju konsensus) di antara pihak-pihak yang berkompeten. Dalam kasus yang berkaitan dengan bahan-bahan penelitian yang bersifat rahasia, dipercaya untuk menginterpretasikan isi konstruksi. Bermacam-macam pengetahuan dapat hadir bersama ketika para penafsir yang sama-sama kompeten tidak sependapat, dan/atau bergantung pada faktor-faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan gender yang membedakan para penafsirnya. Berbagai konstruksi ini tunduk pada revisi yang berkelanjutan, dengan perubahan yang hampir bisa dipastikan terjadi ketika konstruksi yang secara relatif berbeda ditempatkan di dalam posisi sejajar dalam sebuah konteks dialektis.Akumulasi ilmu pengetahuan. Dalam pandangan teori kritis, pengetahuan tidak berakumulasi dalam pengertian mutlak, melainkan tumbuh dan berubah melalui proses revisi historis yang berlangsung secara dialektis, berkelanjutan mengikis ketidaktahuan dan kesalahpahaman serta meningkatkan pemahaman yang lebih matang. Genaralisasi dimungkinkan bila campuran lingkungan dan nilai-nilai sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan gender mirip/sama di seluruh setting. Konstruktivisme melihat pengetahuan berakumulasi hanya dalam satu pengertian relatif melalui pembentukan berbagai konstruksi yang semakin matang dan canggih melalui proses hermeneutis/dialektis, seiring dengan berbagai macam konstruksi yang diletakkan dalam proses sejajar. Suatu mekanisme penting untuk memindahkan ilmu pengetahuan dari satu setting ke setting yang lain adalah modal pengalaman sendiri, yang sering kali diperoleh melalui laporan-laporan studi kasus.Kriteria yang layak dipakai untuk menilai kebaikan atau kualitas sebuah penelitian dalam teori kritis adalah keterposisian historis penelitian; artinya, kriteria tersebut mempertimbangkan gejala awal sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan gender dari situasi yang diteliti, batas yang memungkinkan tindakan penelitian dalam mengikis ketidaktahuan dan kesalahpahaman, dan batas yang dapat dijangkaunya untuk menciptakan stimulus yang mendorong dilakukannya tindakan, yakni mengubah struktur yang ada.Dalam konstruktivisme, dua kumpulan kriteria telah diajukan: kriteria kelayakan kredibilitas (sejalan dengan validitas internal), sifat dapat dipindahkan (sama dengan validitas eksternal), dependabilitas (mirip dengan reliabilitas), dan konformabilitas (mirip dengan objektivitas); dan kriteria keotentikan kewajaran, keontetikan ontologisme (memperbesar konstruksi personal), keotentikan edukatif (mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang berbagai konstruksi orang lain), keotentikan katalitis (menimbulkan stimulus terhadap tindakan), dan keotentikan taktis (memberdayakan tindakan).Kriteria yang pertama menggambarkan usaha awal untuk memecahkan persoalan kualitas bagi konstruktivisme, meskipun kriteria ini telah diterima dengan baik, namun kemiripannya dengan kriteria positivis menjadikannya diragukan. Kriteria yang kedua mengalami tumpang tindih hingga kadar tertentu, dengan kumpulan kriteria teori kritis namun berhasil melampauinya, terutama keotentikan ontologis dan keotentikan edukatif. Meskipun demikian, isu tentang kriteria kualitas dalam konstruktivisme belum terpecahkan dengan baik, sehingga kritik selanjutnya masih dibutuhkan.Dalam teori kritis dan konstruktivisme, nilai memiliki peran yang penting; nilai dipandang sebagai sesuatu yang tak bisa dihindari dalam membentuk dan menciptakan hasil-hasil penelitian. Selain itu, sekalipun memungkinkan, tindakan mengenyampingkan nilai tentulah tidak akan didukung karena tindakan ini berlawanan dengan kepentingan audiens yang lemah dan rentan, yang konstruksi aslinya (emik) layak memperoleh pertimbangan yang sama dengan audiens yang lain, yakni audiens dan peneliti (etik) yang lebih berkuasa. Konstruktivisme, yang memandang peneliti sebagai pelaksana dan fasilitator proses penelitian, lebih berpeluang memberi penekanan pada point ini daripada teori kritis yang cenderung menyeret peneliti ke dalam peran yang lebih otoritatif.Fungsi dan peran etika dalam penelitian. Dalam paradigma teori kritis, etika hampir lebih berciri intrinsik, sebagaimana yang tersirat melalui kesungguhan untuk menghilangkan ketidaktahuan dan kesalahpahaman serta mempertimbangkan sepenuhnya nilai dan keterposisian historis dalam proses penelitian. Dengan demikian, ada kecenderungan moral bahwa peneliti menjadi penyingkap misteri, bukannya penipu. Berbagai pertimbangan ini tidak lantas mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, namun memang memunculkan penghambat proses tertentu sehingga lebih mempersulit perilaku tak etis tersebut. Pada paradigma konstruktivisme, etika juga merupakan hal yang intrinsik karena penyertaan nilai-nilai partisipan dalam penelitian; mulai dengan berbagai konstruksi responden yang sudah ada dan bergerak ke arah peningkatan kematangan dan kecanggihan konstruksinya sekaligus konstruksi peneliti. Ada suatu dorongan kecenderungan proses ke arah penyingkapan rahasia; tindakan menyembunyikan maksud peneliti sungguh berbahaya bagi tujuan penyingkapan dan pengembangan konstruksi. Sebagai tambahan, metodologi hermeneutis/dialektis memberikan pelindung yang kuat, namun tidak kebal untuk mencegah muslihat. Tetapi, interaksi pribadi yang akrab yang dituntut oleh metodologi bisa jadi memunculkan berbagai persoalan khusus dan sering kali rumit menyangkut kerahasiaan dan anonimitas, di samping berbagai kesualitan antar pribadi lainnya.Suara peneliti adalah suara intelektual transformatif (Giroux, 1988), yang telah memperluas kesadarannya sehingga berada dalam posisi yang siap untuk melawan ketidaktahuan dan kesalahpahaman. Perubahan menjadi mudah seiring dengan upaya pengembangan wawasan yang lebih besar tentang seluk-beluk persoalan yang akan dilakukan oleh individu-individu (alam dan batas eksplorasi terhadapnya) dan yang terdorong untuk menyelesaikannya. Pada konstruktivisme, suara peneliti adalah suara partisipan yang penuh empati/semangat (Lincoln, 1991) yang secara aktif terlibat dalam upaya mempermudah rekonstruksi multi-pesan konstruksinya sendiri, demikian pula dengan konstruksi multi-pesan dari partisipan yang lain. Perubahan menjadi mudah seiring dengan terbentuknya rekonstruksi dan individu-individu yang didorong untuk memecahkannya.Implikasi paradigma terhadap pelatihan para peneliti baru. Menurut paradigma teori kritis dan konstruktivisme, pertama-tama, para peneliti baru harus diperkenalkan ulang dengan pandangan ilmu pengetahuan yang diterima yang telah mereka alami secara intens sebelumnya. Pengenalan ulang tersebut tidak dapat dilakukan tanpa pembelajaran total tentang berbagai sikap dan teknik yang berlaku pada positivisme dan post-positivisme. Calon peneliti harus menghargai berbagai perbedaan paradigma, dan dalam konteks tersebut, menguasai metode kualitiatif sekaligus kuantitatif. Metode kualitatif sangat penting karena perannya dalam melaksanakan metodologi dialogis/dialektis atau hermeutis/dialektis; sedangkan metode kuantitatif dinilai penting karena dapat memainkan peran informasional yang sangat berguna dalam seluruh paradigma. Mereka juga harus dibantu untuk memahami sejarah dan struktur sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan gender yang berperan selaku lingkungan/konteks bagi penelitian mereka, dan untuk menyertakan nilai-nilai alturisme dan pemberdayaan ke dalam penelitian mereka.Potensi konflik antar paradigma dan upaya untuk menyatukan pandangan yang berbeda ke dalam suatu kerangka konseptual tunggal. Para penganut dua paradigma ini sama-sama menegaskan ketidaksepadanan antarparadigma, meskipun terdapat kemungkinan untuk kesepadanan keduanya. Kepercayaan dasar dari paradigma-paradigma tersebut diyakini secara esensial saling bertentangan. Bagi kaum konstruktivis, bahwa ada realitas yang nyata atau bisa juga tidak (meskipun seorang peneliti ingin menyelesaikan masalah ini secara berbeda dalam mempertimbangkan dunia fisik versus dunia manusia), dan karenanya, konstruktivisme dan positivisme/post-positivisme secara logika tidak dapat diakomodasi lebih dari kemampuan akomodasi gagasan tentang rumah (flat) versus bumi yang bulat, secara logika. Bagi para ahli teori kritis dan kaum konstruktivis, penelitian bisa jadi bebas nilai atau juga tidak; dan lagi-lagi, akomodasi logis tampaknya adalah hal yang tak mungkin. Realisme dan relativisme, kebebasan nilai dan keterikatan nilai, tidak dapat hadir bersama dalam suatu sistem metafisis yang konsisten secara internal, yang syarat konsistensinya pada dasarnya dipenuhi oleh masing-masing calon paradigma. Pemecahan dilema ini secara otomatis menunggu munculnya metaparadigma yang memandang paradigma lama, paradigma yang terakomodasi bukannya kurang benar, namun semata-mata tidak relevan.Hegemoni dan pengaruh yang paling besar. Para penganut teori kritis dan dan konstruktivisme masih mencari pengakuan dan sumber masukan dana. Sepanjang dasawarsa lalu, semakin memungkinkan bagi mereka untuk memperoleh dukungan, seperti yang dibuktikan dengan bertambahnya jumlah makalah penting yang masuk ke dalam berbagai jurnal dan pertemuan profesional, perkembangan berbagai outlet jurnal baru, pertumbuhan akseptabilitas berbagai disertasi kualitatif, penyertaan berbagai pedoman kualitatif oleh sejumlah lembaga dan program pendanaan, dan semacamnya. Namun, dengan semua peluangnya, teori kritis dan konstruktivisme masih terus memainkan peran sekunder, meskipun penting dan secara progresif lebih berpengaruh, pada masa yang segera tiba.Kekhasan para penganut konstruktivisme adalah ide-ide objektivisme, realisme empiris, kebenaran objektif, dan esensialisme. Karin Knorr-Cetina (1981) menjelaskan bahwa bagi kalangan objektivis, dunia terdiri atas fakta-fakta, dan tujuan ilmu pengetahuan adalah memberikan penjelasan yang gamblang tentang gambaran dunia. Kalangan konstruktivis berpegang teguh pada pandangan yang sebaliknya, bahwa apa yang kita pahami sebagai pengetahuan dan kebenaran objektif merupakan hasil perspektif. Pengetahuan dan kebenaran diciptakan, tidak ditemukan oleh pikiran. Mereka menekankan karakter realitas yang jamak dan lentur jamak dalam pengertian bahwa realitas bisa diungkapkan dalam berbagai sistem simbol dan bahasa; lentur dalam pengertian bahwa realitas bisa direntangkan dan dibentuk sesuai dengan tindakan-tindakan bertujuan dari para pelaku-manusia yang juga memiliki tujuan.Kalangan konstruktivis adalah antiesensialis. Mereka menyatakan bahwa apa yang kita anggap sebagai jenis-jenis yang self-evident, benar dengan sendirinya, dalam hal ini pria, perempuan, kebenaran diri, sesungguhnya adalah hasil praktik-praktik diskursif yang rumit. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Diana Fuss (1989):Apa yang dipertaruhkan oleh kalangan konstruksionis adalah sistem-sistem representasi, praktik-praktik sosial dan material, aturan-aturan diskursus, dan efek-efek ideologis. Singkatnya, yang paling utama, kalangan konstruksionis menekuni produksi dan pengorganisasian perbedaan-perbedaan, dan oleh karena itu, mereka menolak pandangan bahwa segala jenis yang esensial atau natural mendahului proses determinasi sosial.
Sementara itu, penelitian kritis tidak pernah segan untuk menunjukkan keterbatasan-keterbatasan penelitian empiris, dengan meminta perhatian pada ketidakmampuan model-model penelitian tradisional untuk lepas dari batas-batas realisme naratif. Proyek penelitian kritis bukan hanya sekedar penyajian ulang empiris terhadap dunia, namun, lebih dari itu, adalah untuk memperlihatkan bahwa penelitian itu sendiri merupakan rangkaian praktik ideologis. Analisis empiris perlu diselidiki untuk menyingkap berbagai kontradiksi dan negasi yang mewujud dalam setiap deskripsi objektif. Para peneliti kritis berpendapat bahwa makna dari sebuah pengalaman atau observasi tidaklah jelas dengan sendirinya. Makna dari pengalaman apapun bergantung pada usaha untuk menafsirkan dan mendefiniskan pengalaman tersebut (Giroux, 1983; McLaren, 1986; Weiler, 1988).Sebagaimana yang dijelaskan oleh Einstein dan Heisenberg, apa yang kita lihat bukanlah apa yang kita lihat, melainkan apa yang kita persepsikan. Pengetahuan yang dihasilkan dari dunia harus diinterpretasikan oleh manusia (pria dan perempuan) yang menjadi bagian dari dunia tersebut. Apa yang kita sebut informasi selalu melibatkan tindak penilaian manusia. Dari perspektif kritis, tindak penilaian ini merupakan sebauh tindakan interpretif. Interpretasi teori, menurut pandangan kaum analis kritis, mencakup pemahaman tentang hubungan antara yang partikuler dengan yang menyeluruh dan antara subjek dengan objek analisis.2


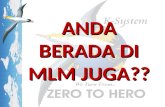




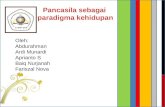
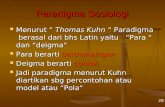









![Perbandingan Metode Pembelajaran E-learning Dan …repository.gunadarma.ac.id/795/1/Perbandingan Metode Pembelajaran … · Literatul Review Darin E. Hartley [Hartley, 2001] yang](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/5abe64707f8b9aa3088ccfd0/perbandingan-metode-pembelajaran-e-learning-dan-metode-pembelajaran-literatul.jpg)



