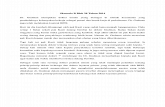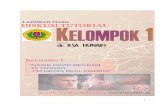Lap. Tutorial Skenario 1 KK.doc
-
Upload
rachmaniar-ratrianti -
Category
Documents
-
view
220 -
download
8
description
Transcript of Lap. Tutorial Skenario 1 KK.doc
LAPORAN TUTORIAL
BLOK KEDOKTERAN KOMUNITAS SKENARIO 1
BAGAIMANA MENGATASI PENINGKATAN
ANGKA KEJADIAN DEMAM DI PULAU SERIBU?
Kelompok A-5
1. Rico Alfredo
(G0012181)2. M. Hafizh Islam S
(G0012119)3. Khairunnisa N. Huda
(G0012107)4. Gilang Yuka S.
(G0012083)5. Wahyu Septianingtyas
(G0012227)6. Krisnawati Intan S.
(G0012109)7. Elfrida Rahma B.
(G0012065)8. Rachmaniar Ratrianti
(G0012169)9. Yuscha Anindya
(G0012239)10. Tika Permata Sari
(G0012221)11. Rima Aji Puspitasari
(G0012187)12. Shofura Azizah
(G0012211)13. Anandita Winadira
(G0012013)Tutor:
Ipop Sjarifah, Dra, M.Si.
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
TAHUN 2015BAB I
PENDAHULUAN
SKENARIO 1
BAGAIMANA MENGATASI PENINGKATAN
ANGKA KEJADIAN DEMAM DI PULAU SERIBU?
Pada bulan Agustus 2013, terdapat peningkatan angka kejadian demam tinggi di Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu. Dilaporkan adanya 427 kasus demam tinggi dalam sebulan dengan Case Fatality Rate (CFR) sebesar 10%. Kasus demam tinggi ini meningkat dibandingkan kasus sebelumnya dimana rata-rata hanya dilaporkan 100 kasus dan jarang menyebabkan kematian. Dinas Kesehatan setempat menurunkan tim untuk melakukan investigasi akan kondisi yang terjadi. Mereka mencurigai adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit malaria. Investigasi dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah penyelidikan KLB.
Malaria memang masih menjadi permasalahan kesehatan di dunia dan di Indonesia. Di Indonesia, prevalensi dan insidensi penyakit malaria di Indonesia masih tinggi, mencapai 417.819 kasus positif pada 2012. Andi mengatakan saat ini 70 persen kasus malaria terdapat di wilayah Indonesia Timur, terutama di antaranya Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Wilayah endemic malaria di Indonesia Timur, ujar Andi, tersebar di 84 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk berisiko 16 juta orang. Andi menjelaskan faktor geografis yang sulit dijangkau dan penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan beberapa penyebab sulitnya pengendalian malaria di wilayah itu. Selain itu faktor host, termasuk status gizi dan adanya penyakit tertentu juga meningkatkan faktor risiko infeksi malaria. Untuk itu, pihaknya juga melakukan pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan pos malaria desa dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) juga digerakkan melalui kecamatan hingga RT-RT setempat untuk menurunkan House Index maupun Container Index pada jentik nyamuk.
Selain itu, juga dilakukan surveillance aktif dan surveillance migrasi. Saat ini pemerintah menargetkan bebas malaria pada tahun 2030. Bebas malaria adalah kondisi dimana Annual Parasite Incident (API), atau insiden parasit tahunan, di bawah satu per 1.000 penduduk dan tidak terdapat kasus malaria pada penduduk lokal selama tiga tahun berturut-turut.
Diadaptasi dari: http://www.voaindonesia.com/content/kasus-malaria-di-indonesia-masih-tinggi/1648507.htmlBAB II
DISKUSI DAN TINJAUAN PUSTAKA
Langkah I: Membaca skenario dan mengklarifikasi kata sulit
1. Case Fatality Rate (CFR) adalah presentase angka kematian oleh sebab penyakit tertentu untuk menentukan kegawatan atau keganasan penyakit tersebut.2. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.3. House Index adalah presentase rumah positif jentik dari seluruh rumah yang diperiksa.4. Container Index adalah presentase tempat air yang terdapat jentik-jentik dari semua tempat air yang diperiksa.5. Surveillance aktif yaitu petugas khusu surveilans melakukan kunjungan berkala ke lapangan untuk mengidentifikasi kasus baru penyakit atau kematian (case finding) dan konfirmasi laporan kasus indeks.6. Surveillance migrasi adalah kegiatan pengambilan darah orang-orang yang menunjukkan gejala malaria klinis yang baru datang dari daerah endemis malaria dalam rangka mencegah masuknya kasus.7. Surveillance adalah suatu kegiatan yang dilakukan terus menerus berupa pengumpulan data secara sistematik, analisis, dan interpretasi data mengenai suatu peristiwa yang terkait dengan kesehatan untuk digunakan dalam tindakan kesehatan masyarakat dalam upaya mengurangi angka kesakitan dan kematian, dan meningkatkan status kesehatan.8. Host adalah pejamu yang terinfeksi oleh agen penyebab infeksi.9. Pos malaria desa merupakan wadah komunikasi dan informasi kesehatan serta pengembangan masyarakat dalam rangka penanggulangan malaria atas dasar swadaya masyarakat.10. Prevalensi adalah jumlah total kasus penyakit tertentu yang terjadi pada waktu tertentu di wilayah tertentu.11. Insidensi adalah tingkat terjadinya kejadian tertentu, seperti jumlah kasus baru penyakit spesifik yang terjadi selama satu masa tertentu pada populasi yang berisiko.12. Annual Parasite Incident (API) adalah jumlah penderita positif malaria per seribu penduduk.13. Bebas malaria adalah kondisi dimana Annual Parasite Incident (API), atau insiden parasit tahunan, di bawah satu per 1.000 penduduk dan tidak terdapat kasus malaria pada penduduk lokal selama tiga tahun berturut-turut.14. Pemberantasan Sarang Nyamuk adalah tindakan yang dilakukan untuk memberantas sarang nyamuk dengan melakukan 3M (mengubur, menguras, menimbun).Langkah II: Menetapkan / mendefinisikan masalah
1. Apakah kriteria dan kategori KLB?
2. Bagaimana langkah langkah penyelidikan KLB?
3. Bagaimana langkah penghitungan CFR? Prevalensi? Insidensi?
4. Bagaimana langkah melakukan surveillance aktif dan surveillance migrasi?
5. Bagaimana langkah penaggulangan KLB?
6. Bagaimana cara menghitung House index dan container index?
7. Bagaimana bentuk pemberdayaan masyrakat oleh Pos Malaria Desa?
8. Apa saja level kemunculan penyakit di suatu wilayah?
9. Mengapa KLB Malaria sering terjadi di Indonesia Timur?
10. Bagaimana cara menghitung API?
11. Bagaimana upaya pemerintah dalam pemberantasan malaria?
12. Bagaimana peran dokter dalam upaya pemberantasan malaria?
13. Apa saja faktor penyebab malaria?
14. Bagaimana epidemiologi malaria?
15. Mengapa prevalensi kasus malaria masih tinggi?
16. Apa saja indikator bebas malaria?
17. Bagaimana langkah pencegahan tahapan suatu penyakit?
Langkah III: Melakukan curah pendapat dan membuat pernyataan sementara mengenai permasalahan (dalam langkah II)
a. Penjelasan mengenai sporadik, endemik, epidemik, dan pandemikSporadik adalah suatu keadaan dimana suatu masalah kesehatan (umumnya penyakit) yang ada di suatu wilayah tertentu frekuensinya berubah-ubah menurut perubahan waktu (Azwar, 1988).
Endemi adalah adalah suatu keadaan dimana suatu masalah kesehatan (umumnya penyakit) frekuensinya pada suatu wilayah tertentu menetap dalam waktu yang lama (Azwar, 1988). Penyakit menular dikatakan endemik apabila penyakit ini timbul secara konstan pada suatu daerah dan populasi tertentu dengan tingkat prevalensi serta insiden yang relatif tinggi (Bonita, 2006).
Epidemi adalah suatu keadaan dimana suatu masalah kesehatan (umumnya penyakit) yang ditemukan pada suatu daerah tertentu dalam waktu yang singkat berada dalam frekuensi yang meningkat (Azwar, 1988). Epidemik adalah timbulnya suatu penyakit atau kondisi tertentu yang melebihi perkiraan pada suatu daerah dan waktu tertentu. batas yang melebihi perkiraan berbeda pada tiap penyakitnya. Hal ini bisa dibandingkan dengan angka kejadian pada bulan atau tahun sebelumnya. Epidemik yang menyebar luas ke daerah lain bisa disebut dengan pandemik (Bonita, 2006)
Pandemi adalah adalah suatu keadaan dimana suatu masalah kesehatan (umumnya penyakit) frekuensinya dalam waktu yang singkat memperlihatkan peningkatan yang amat tinggi serta penyebarannya telah mencakup suatu wilayah yang amat luas (Azwar, 1988).
b. Kejadian Luar Biasa dan Wabah
Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu (PP Menkes RI No.949/MENKES/SK/VII/2004).
Wabah adalah berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada kejadian yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Menteri menetapkan dan mencabut daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah (PP Menkes RI No.949/MENKES/SK/VII/2004).
Kriteria KLB (Keputusan Dirjen PPM No.451/91):
1) Timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal.
2) Peningkatan kejadian penyakit terus menerus selama 3 kurun waktu berturut- turut menurut penyakitnya (jam, hari, minggu).
3) Peningkatan kejadian penyakit/ kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, hari, minggu, tahun).
4) Jumlah penderita baru dalam satu bulan naik 2 kali lipat/ lebih dibandingkan angka rata- rata perbulan tahun sebelumnya.
Wabah harus mencakup (UU Wabah 1969):
1) Jumlah kasus yang besar
2) Derah yang luas
3) Waktu yang lebih lama
4) Dampak yang ditimbulkan berat
Menurut UU No.6 Tahun 1962 tentang Wabah. Wabah meliputi:
Penyakit-penyakit karantina berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-undang No.2 tahun 1962 tentang Karantina Udara.
Penyakit seperti :
Tifus perut (Typhus abdominalis)
Para-tifus A, B dan C,
Disentri (mejan) basili (Dycenteriabacillaris),
Radang hati menular (Hepatitisinfectiosa),
Para-cholera Eltor,
Diphtheria,
Kejang tengkuk (Meningitiscerebrospinalis epidemica),
Lumpuh kanak-kanak (Poliomyelitisanterior acuta).
Penyakit lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
d. Menjelaskan perhitungan dan tingkatan API
API (Annual Parasite Incidence) merupakan jumlah kasus malaria tiap 1.000 populasi per tahun. API menggambarkan ukuran yang paling dapat dipakai untuk mengukur risiko infeksi. Banyak kebijakan yang didasarkan pada API dalam menghitung risiko infeksi yang ada. Dalam statistik sering digunakan untuk membandingkan risiko infeksi antara komunitas populasi tertentu, daerah, provinsi, dan negara.
Cara pengukuran API sebagai berikut:
API = Kasus infeksi yang dilaporkan x 1.000
Jumlah penduduk
Dengan hasil pengolahan data, maka selanjutnya dibuat data stratifikasi dengan wilayah puskesmas dengan batas desa. Kemudian dibagi daerah itu berdasarkan reseptivitas, infrastruktur data entomologi, pemberantasan vektor, dan API per desa. API dikelompokkan sebagai berikut :
-HCI (High Case Incidence) API > 5 %o
-MCI (Moderate Case Incidence) API 1 - < 5 %o
-LCI (Low Case Incidence) API < 1 %o (Doolan, 2002).
e. Menjelaskan cara menghitung House Index (HI), Container Index (CI), dan Case Fatality Rate (CFR)
House Index (HI) adalah persentase rumah positif jentik dari seluruh rumah yang diperiksa, HI menggambarkan penyebaran nyamuk di suatu wilayah.House Index (HI) = Jumlah rumah positif jentik : jumlah rumah yang diperiksa x 100%Nilai HI dikatakan baik apabila 5 % Container Index (CI) adalah persentase container positif jentik dari seluruh container yang diperiksaContainer Index (CI) = Jumlah penampungan air/kontainer positif jentik : jumlah penampungan air/kontainer yang diperiksa x 100%
Nilai CI dikatakan baik apabila < 2 % Case Fatality Rate (CFR) adalah persentase angka kematian oleh karena penyakit tertentu, untuk menentukan kegawatan/keganasan penyakit dalam waktu tertentuCase Fatality Rate (CFR) = Jumlah kematian penyakit : jumalh kasus penyakit x 100%
Langkah IV: Menginventarisasi permasalahan secara sistematis dan pernyataan sementara mengenai permasalahan pada langkah III
Langkah V: Merumuskan tujuan pembelajaran
1. Menjelaskan langkah langkah penyelidikan KLB , kategori KLB dan penanggulangan KLB?
2. Menjelaskan langkah melakukan surveillance aktif dan surveillance migrasi?
3. Menjelaskan bentuk pemberdayaan masyrakat oleh Pos Malaria Desa?
4. Menjelaskan upaya pemerintah dan pekerja di bidang kesehatan dalam pemberantasan malaria?
5. Menjelaskan indikator bebas malaria?
Langkah VI: Mengumpulkan informasi baru dengan belajar mandiriLangkah VII: Melaporkan, membahas dan menata kembali informasi baru yang diperoleh
Langkah Penyelidikan KLB
1. Persiapan penelitian lapangan.
2. Menetapkan apakah kejadian tersebut suatu KLB.
3. Memastikan Diagnosis Etiologis.
4. Mengidentifikasikan dan menghitung kasus atau paparan.
5. Mendeskripsikan kasus berdasarkan orang, waktu dan tempat.
6. Membuat cara penanggulangan sementara dengan segera (jika diperlukan).
7. Mengidentifikasi sumber dan cara penyebaran.
8. Mengidentifikasi keadaan penyebab KLB.
9. Merencanakan penelitian lain yang sistimatis.
10. Menetapkan saran cara pencegahan atau penanggulangan.
11. Menetapkan sistim penemuan kasus baru atau kasus dengan komplikasi.
12. Melaporkan hasil penyidikan kepada instansi kesehatan setempat dan kepada sistim pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.
Kategori KLB
1. Kolera
2. Pes
3. Demam Berdarah Dengue
4. Campak
5. Polio
6. Difteri
7. Pertusis
8. Rabies
9. Malaria
10. Avian Influenza H5N1
11. Antraks
12. Leptospirosis
13. Hepatitis
14. Influenza A baru (H1N1)/Pandemi 2009
15. Meningitis
16. Yellow Fever
17. Chikungunya
Penanggulangan KLB
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan
Pasal 13
1) Penanggulangan KLB/Wabah dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
2) Penanggulangan KLB/Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyelidikan epidemiologis;
b. penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
c. pencegahan dan pengebalan;
d. pemusnahan penyebab penyakit;
e. penanganan jenazah akibat wabah;
f. penyuluhan kepada masyarakat; dan
g. upaya penanggulangan lainnya.
3) Upaya penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain berupa meliburkan sekolah untuk sementara waktu, menutup fasilitas umum untuk sementara waktu, melakukan pengamatan secara intensif/surveilans selama terjadi KLB serta melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan secara keseluruhan.
Upaya penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan jenis penyakit yang menyebabkan KLB/Wabah.
Faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia masih tinggi kasus malaria terutama di Indonesia Timur dan penyebab pemerintah menargetkan bebas malaria per daerah berbeda-beda
Wilayah Indonesia Timur masih memiliki kasus malaria yang tinggi disebabkan oleh:
a. Faktor internal (dari sisi penderita malaria)
1) Tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia Timur yang masih rendah.
2) Masyarakat yang tinggal di daerah berisiko malaria memiliki persepsi yang berbeda mengenai konsep sehat-sakit dengan yang dimiliki oleh petugas kesehatan.
3) Masyarakat beranggapan bahwa malaria bagian dari kehidupan sehari-hari yang wajar terjadi karena merupakan penyakit yang diderita secara turun-temurun di keluarga sehingga penderita tidak merasa khawatir.
b. Faktor eksternal
1) Berupa keadaan sosial, ekonomi dan pembangunan infrastruktur di daerah Indonesia Timur yang masih tertinggal.
2) Sarana seperti tempat pelayanan kesehatan masih sulit terjangkau oleh masyarakat.
Penyebaran malaria di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:
1) Perubahan lingkungan yang tidak terkendali dapat menimbulkan tempat perindukan nyamuk malaria.
2) Banyaknya nyamuk Anopheles sp. yang telah dikonfirmasi sebagai vektor malaria (17 spesies), dari berbagai macam habitat.
3) Mobilitas penduduk yang relatif tinggi dari dan ke daerah endemik malaria.
4) Perilaku masyarakat yang memungkinkan terjadinya penularan.
5) Semakin meluasnya penyebaran parasit malaria yang telah resisten terhadap obat anti malaria.
6) Terbatasnya akses pelayanan kesehatan untuk menjangkau seluruh desa yang bermasalah malaria, karena hambatan geografis, ekonomi, dan sumber daya.
7) Malaria terjadi di daerah terpencil yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan masyarakat.
Pemantauan dan analisa data yang masih lemah di semua jenjang sehingga tindakan yangdilakukan kurang optimal.Indikator bebas malaria dan penentuan indikator bebas suatu penyakit
Menurut KMK Nomor 293/Menkes/Sk/Iv/2009, suatu wilayah dikatakan bebas malaria jika pada kabupaten/kota atau provinsi yang sudah tidak ditemukan lagi penderita dengan penularan setempat (kasus indigenous) selama 3 tahun berturut-turut dan dijamin adanya pelaksanaan surveilans yang baik. Daerah tersebut dapat mengusulkan/ mengajukan ke pusat, untuk dinilai apakah sudah layak mendapatkan Sertifikat Eliminasi Malaria dari Pemerintah (Departemen Kesehatan RI).Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat bebas malaria adalah:
a. Surveilans dilaksanakan dengan baik termasuk surveilans migrasi dan dapat menjangkau seluruh wilayah eliminasi.
b. Adanya register kasus malaria yang mencakup wilayah eliminasi secara lengkap.
c. Unit pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta mampu mendeteksi kasus secara dini dan mengobati secara tepat.
d. Puskesmas dan dinas kesehatan setempat mampu menindaklanjuti kasus impor yang ditemukan.
e. Tersedianya mikroskopis dengan kualitas pemeriksaan sediaan darah yang baik terutama di wilayah reseptif.
f. Setiap kasus positif dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menentukan asal penularan.
g. Adanya peraturan daerah atau peraturan perundangan lain yang mendukung dan menjamin tersedianya dana secara berkesinambungan untuk pemeliharaan eliminasi malaria (mencegah penularan kembali).
h. Adanya sosialisasi/penyuluhan yang berkesinambungan tentang pencegahan malaria kepada wisatawan/pendatang untuk menghindari penularan malaria, antara lain dengan menggunakan kelambu berinsektisida, repellent, pengobatan profilaksis.
i. Di wilayah yang reseptivitasnya tinggi dilakukan surveilans vektor, termasuk efikasi insektisida dan resistensi vektor.
j. Berfungsinya SKD KLB dan mampu melakukan penanggulangan secara cepat bila terjadi KLB.
k. Bila diperlukan adanya koordinasi lintas batas kabupaten / kota dan provinsi.
Terjadinya KLB malaria oleh P. Falciparum dan adanya penularan kembali malaria di wilayah yang telah dinyatakan bebas malaria, harus segera dilaporkan kepada WHO. Indikasi terjadinya penularan kembali malaria di suatu fokus adalah adanya 3 atau lebih kasus introduced dan atau kasus indigenous di wilayah fokus tersebut, dalam periode waktu 2 tahun berturut-turut untuk P. Falciparum dan 3 tahun berturut-turut untuk P. vivax.
Eliminasi malaria menuju bebas malaria 2030
Adapun pelaksanaan pengendalian malaria menuju eliminasi dilakukan secara bertahap dari satu pulau atau beberapa pulau sampai seluruh pulau tercakup guna terwujudnya masyarakat yang hidup sehat yang terbebas dari penularan malaria sampai tahun 2030 dengan tahapan sebagai berikut:
1. 2010: Eliminasi malaria di DKI, Bali dan Barelang Binkar, dimana seluruh sarana pelayanan kesehatan telah mampu melakukan konfirmasi laboratorium kasus malaria yang rendah.
2. 2015: Pembebasan Jawa, Aceh dan Kepulauan Riau.
3. 2020: Pembebasan Sumatera, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi.
4. 2030: Pembebasan Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTTPencegahan sesuai perjalanan penyakit termasuk pencegahan malaria
Pencegahan dapat dilakukan sesuai tahapan perjalanan penyakit, terdapat empat jenis pencegahan yaitu :
a. Pencegahan primordial : Tujuan : untuk mencegah timbulnya pola hidup berisiko tinggi. Contoh: olahraga teratur, mencegah gaya hidup merokok, mencegah pencemaran udara, mencegah pola makan tinggi lemak.
b. Pencegahan primer : Tujuan : mencegah agar penyakit tidak terjadi dengan mengendalikan agent dan faktor determinan. Contoh : Pemberian suplemen vitamin A pada anak-anak secara rutin dan berkala, Pemberian semua keperluan dasar yang memenuhi syarat kesehatan.
c. Pencegahan sekunder : Tujuan : mengurangi keparahan penyakit dengan melakukan diagnosis dan pengobatan dini. Untuk penyakit tertentu dilakukan penapisan atau screening. Kriteria untuk melakukan screening: a) Penyakit (Parah, Prevalensi tinggi pada fase awal, Perjalanan penyakit telah dimengerti betul, Periode antara sakit ringan dan sakit keras cukup lama) b) Diagnosis (Fasilitas tersedia, Cara pengobatan dapat diterima masyarakat dan efektif) c) Pengujian (Sensitif dan spesifik, mudah, murah, aman, dapat diterima dan dipercaya).
d. Pencegahan tersier : Tujuan : mencegah terjadinya cacat, Contoh : Pengobatan penderita, Rehabilitasi penderita.
Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit malaria yaitu di antaranya:
a. Menghindari gigitan nyamuk dengan memakai baju tertutup
b. Menggunakan krim anti nyamuk
c. Memasang kelambu anti nyamuk
d. Jika akan bepergian ke tempat di mana banyak nyamuk malaria, sebaiknya berkonsultasi dahulu dengan dokter
e. Menghindari keluar rumah setelah senja
f. Menyemprotkan obat nyamuk di kamar tidur dan isi rumah
Pengendalian malaria secara kimia
Pengendalian kimia dapat menggunakan kelambu berinsektisida, indoor residual spray, repellent, insektisida rumah tangga dan penaburan larvasida (Kementerian Kesehatan).
a. Repellent
Repellent adalah bahan-bahan kimia yang mempunyai kemampuan untuk menjauhkan serangga dari manusia sehingga dapat dihindari gigitan serangga atau gangguan oleh serangga terhadap manusia. Repellent digunakan dengan cara menggosokkannya pada tubuh atau menyemprotkannya pada pakaian, oleh karena itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu tidak mengganggu pemakainya, tidak melekat atau lengket, baunya menyenangkan pemakainya dan orang sekitarnya, tidak menimbulkan iritasi pada kulit, tidak beracun, tidak merusak pakaian dan daya pengusir terhadap serangga hendaknya bertahan cukup lama. DEET (N,N-diethyl-mtoluamide) adalah salah satu contoh repellent yang tidak berbau, akan tetapi menimbulkan rasa terbakar jika mengenai mata, luka atau jaringan membranous (Soedarto, 1992).
b. Penaburan Larvasida
Pemberantasan nyamuk Anopheles secara kimiawi dapat dilakukan dengan menggunakan larvasida yaitu zat kimia yang dapat membunuh larva nyamuk, yang termasuk dalam kelompok ini adalah solar/minyak tanah, parisgreen, temephos, fention, altosid dll.Selain zat-zat kimia yang disebutkan di atas dapat juga digunakan herbisida yaitu zat kimia yang mematikan tumbuhtumbuhan air yang digunakan sebagai tempat berlindung larva nyamuk (Hiswani, 2004).
c. Kelambu berinsektisida/ LLIN
Menurut WHO dalam Guideline for Laboratory and Field Testing of LLINs adalah kelambu berinsektisida (kelambu yang sudah dilapisi racun serangga) buatan pabrik yang diharapkan dapat mempertahankan aktifitas biologi sampai jumlah minimum dari standar WHO untuk pencucian, dan periode waktu minimum di bawah kondisi lapangan. LLINs diharapkan dapat mempertahankan aktifitas biologinya minimal 20 kali pencucian menurut standart WHO di bawah kondisi Laboratorium dan tiga yang direkomendasikan penggunaannya dalam kondisi lapangan. Bahan dasar pembuatan kelambu LLINs yang beredar di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu polyester dan polyethylene.Pos Malaria Desa Pos Malaria Desa adalah wadah pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian malaria yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
Tujuan :
1. Meningkatkan jangkauan penemuan kasus malaria melalui peran aktif masyarakat dan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan malaria
Posmaldes diperlukan karena:
1. Sekitar 45% dari desa endemis malaria merupakan daerah terpencil (transportasi dan komunikasi sulit, akses pelayanan kesehatan rendah, sosial ekonomi masyarakat rendah, cakupan penemuan kasus malaria oleh Puskesmas rendah, pengobatan tidak sempurna karena banyak obat malaria dijual bebas)
2. Posmaldes merupakan embrio berbagai bentuk UKBM lainnya
Tugas Kader malaria:
1. Menemukan kasus malaria klinis
2. Merujuk penderita
3. Melakukan penyuluhan dan upaya pencegahan bersama masyarakat
4. Membuat catatan hasil kegiatan
5. Kader mendapat pelatihan dan dilengkapi dengan posmaldes kit dan media penyuluhan malaria.
Pokok Kegiatan Polmaldes
1. Penemuan dini dan pengobatan penderita
2. Meningkatkan akses pelayanan yang berkualitas (konfirmasi dengan mikroskop atau RDT).
3. Pemberdayaan dan penggerakan masyarakat
4. Meningkatkan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
5. Menggalang kemitraan
6. Meningkatkan sistem surveilans
7. Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi
8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pada skenario ini terdapat peningkatan angka kejadian demam tinggi di Kepulauan Seribu dalam sebulan, sehingga dicurigai adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit malaria. Untuk mengetahui secara lebih pasti, dibutuhkan investigasi dengan menerapkan langkah-langkah penyelidikan KLB, sehingga diketahui apakah permasalahan tersebut termasuk kepada kategori KLB atau tidak sehingga dapat dilakukan tindakan selanjutnya untuk penanggulangan KLB dan menurunkan prevalensi serta insidensi penyakit malaria.B. SARAN
1. Untuk Skenario
Materi di skenario sudah baik. Keterangan pada kasus di skenario sudah cukup lengkap sehingga mahasiswa dapat belajar lebih terarah.
2. UntukMahasiswa
Kegiatan diskusi tutorial kelompok kami telah berjalan cukup lancar. Mahasiswa cukup berperan aktif dalam diskusi ini. Tutor juga mengarahkan diskusi sehingga LO atau tujuan pembelajaran dapat tercapai.
DAFTAR PUSTAKA
Azwar , Azrul (1988). Pengantar Epidemiologi. Jakarta : P.T. Binarupa Aksara..
Bonita R, Beaglehole R, Kjellsrom T (2006). Basic Epidemiology (2nd ed). Geneva: WHO.
Doolan, D L (2002). Malaria methods and protocols. New Jersey: Humana Press Inc.
Kementerian Kesehatan RI (2011). Buku Saku Eliminasi Malaria. http://www.pppl.depkes.go.id/_asset/_download/Buku_saku_menuju_eliminasi_malaria.pdf - diakses September 2015Keputusan Menteri Kesehatan RI (2009). Eliminasi Malaria. http: pppl.depkes.go.id/_asset/_regulasi/KEPMENKES_NO_293_THN_2009_TTG_ELIMINASI_MALARIA.pdf diakses pada September 2015Upa, E.E.P., Laure, E. (2007). Studi Tentang Peran Kader Pos Malaria Desa (POSMALDES) di Kota Kupang. Media Kesehatan Masyarakat Vol. 03 No. 02. Kupang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa CendanaRiwayat Alamiah Penyakit
Faktor Host, Agent, environtment
Peningkatan kejadian Malaria
KLB Malaria
Langkah Penanganan wabah
Bebas Malaria
Pemberantasan Sarang Nyamuk
Endemik Malaria
Prevalensi Malaria tinggi
Attack Rate Case Fatality Rate