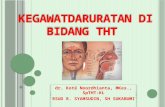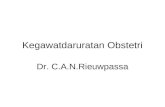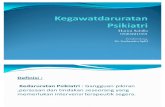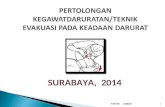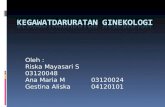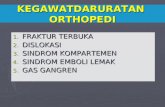Kegawatdaruratan Bm
-
Upload
maulia-sanaz-septiari -
Category
Documents
-
view
140 -
download
0
description
Transcript of Kegawatdaruratan Bm

Tugas Bedah Mulut 2
Kegawatdaruratan Non-Bedah
Disusun oleh:
Citra Faiza Putri 04101004045
Muthiara Praziandite 04101004046
Wahyu Purnama Opita 04101004047
Tety Verianti 04101004048
Rhezza Dwi Febrian 04101004049
Jingga Titania 04101004050
Indira Tri Amirah 04101004051
Tri Susanti 04101004052
Maria Sri Murni 04101004053
Pratiwi Ramadhan 04101004054
Program Studi Kedokteran GigiFakultas KedokteranUniversitas Sriwijaya
2012/2013

PENDAHULUAN
Kegawatdaruratan adalah suatu kondisi yang mendesak yang membutuhkan
penanganan dengan segera untuk mempertahankan hidup dan mengurangi resiko
kematian dan kecacatan. Kondisi seperti ini dapat saja terjadi pada praktik dokter
gigi, bahkan sering terjadi. Ada berbagai perlengkapan darurat pada praktik bedah
mulut untuk menangani kondisi tersebut.
Insidensi gawat darurat pada bedah lebih tinggi daripada non-bedah,
karena:
1. tindakan bedah sering merupakan suatu stress-provoking
2. banyaknya medikasi yang diberikan pada tindakan bedah
3. waktu pelaksanaan tindakan bedah yang lama
Penatalaksanaan dasar dalam kegawatdaruratan adalah akronim PABCD yaitu
position, airway, breathing, circulation, dan definitive care (pada basic life support
biasa disebut dengan defibrillation). Perlu pula ditentukan apakah pasien dalam
keadaan sadar atau tidak, bila pasien tidak sadar maka tidak ada respons terhadap
stimulasi, sehingga hindari tindakan untuk menggerakkan dan berteriak.
Manajemen pencegahan kegawatdaruratan adalah dengan Assesment yang
tepat, yaitu medical history yang akurat, pemeriksaan vital sign dan pemeriksaan
fisik. Dalam makalah ini akan membahas mengenai beberapa mengenai kegawat
daruratan bedah, baik itu kondisi nya maupun cara menanganinya.
Perlengkapan darurat pada praktik bedah mulut
I. Oksigen Darurat
Pada setiap praktik dokter harus selalu tersedia sumber oksigen. Jika ruang
praktik terletak pada bangunan yang bertingkat lebih dari satu, maka tabung
oksigen darurat harus berbentuk portable atau harus ada satu untuk tiap tingkat.
Tabung oksigen sebaiknya silinder berukuran 170 liter, ukuran C. Katup pengatur
reduksi, kantung pernapasan (Amubag), dan masker wajah harus sudah
dipersiapkan. Kunci untuk membuka katup pada silinder harus diletakkan pada
tabung. Sebaiknya disediakan juga perangkat pernapasan orofaringeal atau Brook.

II. Obat-obatan Darurat
Vial injeksi adrenalin tartrat BP (adrenalin 1:1000)
2 botol hidrokortison sodium suksinat, masing-masing 100 mg
2 ampul klorpeniramin maleat (Piriton) 10 mg
Ampul air steril 2 cc untuk injeksi
50 ml injeksi glukosa kuat BP 50% w/v
Glukagon hidroklorid 1 mg
4 vial diazepam BP 10 mg dalam 2 ml untuk injeksi IV
2 spuit disposibel steril 200 cc
2 spuit disposibel steril 2 cc
Kanula kupu-kupu 21 gauge.
Prinsip ABCDE dalam Penanganan Pasien Trauma
A : Airway with cervical spine control
Mempertahankan jalan nafas baik secara manual ataupun menggunakan alat
bantu. Yang perlu diperhatikan disini adalah tindakan manipulasi pada leher harus
tetap mempertahankan stabilitas tulang belakang.
B: Breathing and ventilation
Menjaga pernafasan atau ventilasi. Hal ini dilakukan misalnya dengan
pemberian oksigen (10-15 liter/menit). Kelainan perifer misalnya aspirasi dan
pneumothoraks dan kelainan sentral misalnya kerusakan pusat nafas di otak dapat
mengakibatkan gangguan pernafasan.
C: Circulation and hemorrhage control
Mengontrol sumber perdarahan dan mempertahankan sirkulasi. Selain itu,
pemberian cairan pada pasien sangatlah penting terutama pada pasien yang
kehilangan banyak darah. gangguan sirkulasi yang paling sering disebabkan oleh
kondisi hipovalemia akibat perdarahan luar, ruptur organ dalam abdomen, trauma
dada, syok septik, dan pneumothoraks.

D: Disability / neurological status
Pemeriksaan untuk mengetahui kemungkinan adanya gangguan neurologis.
Mislanya dapat menggunakan skala koma Glasgow (GCS).
E: Exposure and environment
Pemeriksaan tubuh pasien secara keseluruhan dan juga menjaga pasien dari
hipotermi. Biasanya yang dilakukan adalah menutup tubuh pasien dengan selimut
hangat (setelah seluruh pakaiannya dibuka) atau menggunakan alat penghangat
khusus.
Tindakan pra-rumah sakit yang dilakukan meliputi:
Menjaga jalan napas pasien
Mengontrol perdarahan
Stabilisasi keadaan umum pasien
Mengontrol perdarahan
Mencegah syok
Imobilisasi pasien
Mencegah terjadinya komplikasi dan cedera sekunder
Mengirim pasien dengan kompetensi yang sesuai secepatnya
A. Stabilisasi Keadaan Umum Pasien
Stabilisasi keadaan umum pasien, dapat dilakukan dengan:
Memposisikan bagian paha dan kaki lebih tinggi dari kepala (autotransfusi)
Substitusi cairan secara intravena
Pemberian obat analgetik yang cukup
Melindungi pasien dari kedinginan
Posisi pasien yang aman adalah posisi samping. Posisi ini dapat digunakan jika
pada pasien tidak dilakukan intubasi atau tidak perlu dilakukan intubasi dan jika
tidak perlu untuk dilakukan resusitasi jantung-paru. Yang perlu diperhatikan pada
fraktur rahang bawah adalah jangan sampai kepala terutama rahang bawah

dijadikan tumpuan. Posisi ini biasanya hanya digunakan sampai pasien
ditransportasi ke rumah sakit terdekat.
B. Menjaga Jalan Pernafasan
Menjaga jalan pernafasan sangat penting karena penyebab utama kematian
pada kasus trauma Oral dan Maksilofasial adalah karena blokade jalan nafas. Pada
fraktur rahang bawah, displacement rahang bawah, lidah, dan ootot-otot dasar
mulut dapat memblokade jalan pernafasan. Hal ini disebabkan karena Mm.
Genioglossi dan oto suprahyoid kehilangan perlekatannya pada bagian ventral dan
sebagai akibatnya akan bergerak jatuh ke belakang dan menutup jalan nafas. Selain
itu, blokade jalan nafas juga dapat disebabkan oleh hematoma, misalnya pasca-
trauma leher.
Manuver Erschmarch dan menarik rahang bawah ke bagian depan dapat
membantu melancarkan jalan pernafasan. Pada keadaan normal, jarak dari dorsal
lidah ke dinding tenggorok adalah 15 mm. dengan membuat posisi kepala
mendongak ke belakang jarak ini bertambah 8 mm dan dengan menarik rahang
bawah ke bagian depan jarak ini dapat bertambah hingga 8 mm lagi. Selain itu,
dapat dilakukan pemasangan pipa orofaringeal (pipa Guedel) atau pipa
nasofaringeal (pipa Wendl) untuk melancarkan jalan nafas.
Manuver Erschmarch
Posisi operator dari arah jam 12 pasien
Pertama, jari telunjuk hingga kelingking kedua tangan memegang bagian
angulus mandibula
Ibu jari diposisikan pada dagu pasien
Rahang bawah didorong ke depan
Ibu jari digunakan untuk membuka mulut
Satu tangan digunakan untuk mempertahankan mulut dalam posisi terbuka
Tangan yang lain dimasukkan dalam mulut untuk inspeksi intraoral
(mengeluarkan protesa, gigi avulsi, dan benda asing lainnya)

Jika telah sampai di rumah sakit dengan peralatan yang memadai trakeostomi
atau laringotomi dapat dilakukan dengan segera, jika memang diperlukan. Kadang
cukup dilakukan pemasangan pipa endotrakea.
Laringotomi (Krikotirotomi)
Laringotomi dilakukan dengan membuat lubang pada membran tirokrikoid
(krikotirotomi). Krikotiromi merupakan tindakan penyelamat pada pasien dalam
keadaan gawat napas. Bahayanya besar tetapi mudah dikerjakan, dan harus
dikerjakan cepat walaupun persiapannya darurat.
Krikotirotomi merupakan kontraindikasi pada anak di bawah usia 12tahun,
demikian juga pada tumor laring yang sudah meluas ke subglotik dan terdapat
laringitis.
Bila kanul dibiarkan terlalu lama maka akan timbul stenosis subglotik karena
kanul yang letaknya tinggi akan mengiritasi jaringan-jaringan di sekitar subglotis,
sehingga terbentuk jaringan granulasi dan sebaiknya diganti dengan trakeostomi
dalam waktu 48 jam.
Teknik krikotirotomi:
Pasien tidur telentang dengan kepala ekstensi pada artikulasi
atlantooksipitalis.
Puncak tulang rawan tiroid mudah diidentifikasi difiksasi dengan jari
tangan kiri.
Dengan telunjuk jari tangan kanan tulang rawan tiroid diraba ke bawah
sampai ditemukan kartilago krikoid. Membran krikotiroid terletak di antara
kedua tulang rawan ini. Daerah ini diinfiltrasi dengan anestetikum
kemudian dibuat sayatan horizontal pada kulit.
Jaringan di bawah sayatan dipisahkan tepat pada garis tengah.
Setelah tepi bawah kartilago terlihat, tusukkan pisau dengan arah ke
bawah.- Kemudian masukkan kanul bila tersedia. Jika tidak, dapat dipakai
pipa plastik untuk sementara

Gambar. Teknik krikotirotomi
Trakeostomi
Trakeostomi adalah suatu tindakan bedah dengan mengiris atau membuat
lubang sehingga terjadi hubungan langsung lumen trakea dengan dunia luar untuk
mengatasi gangguan pernapasan bagian atas.
Indikasi trakeostomi adalah:
o Mengatasi obstruksi laring.
o Mengurangi ruang rugi (dead air space) di saluran pernapasan atas.
o Mempermudah pengisapan sekret dari bronkus.
o Untuk memasang alat bantu pernapasan (respirator).
o Untuk mengambil benda asing di subglotik, apabila tidak mempunyai
fasilitas bronkoskopi
Keuntungan trakeostomi yaitu:
o Dapat dipakai dalam waktu lama.
o Trauma saluran napas tidak ada.
o Penderita masih dapat berbicara sehingga kelumpuhan otot laring dapat
dihindari.
o Penderita merasa enak dan perawatan lebih mudah
o Penderita dapat makan seperti biasa.

o Menghindari aspirasi, menghisap sekret bronkus.
o Jalan napas lancar, meringankan kerja paru.
Kerugian trakeostomi, yaitu:
Tindakan lama.
Cacat dengan adanya jaringan sikatrik.
Jenis irisan trakeostomi ada dua macam:
Irisan vertikal di garis median leher.
Irisan horizontal.
Berdasarkan jenis trakeostomi:
o Trakeostomi letak tinggi, yaitu di cincin trakea 2-3.
o Trakeostomi letak tengah, yaitu setinggi trakea 3-4.
o Trakeostomi letak rendah, yaitu setinggi cincin trakea 4-5.
Untuk perawatan trakeostomi, yang harus diperhatikan adalah:
1. Kelembaban udara masuk.
Dapat dilakukan dengan uap air basah hangat, Nebulizer, Kassa steril yang
dibasahi diletakkan di permukaan stoma.
2. Kebersihan dalam kanul.
Jangan tersumbat oleh sekret, dianjurkan disuksion ½-1 jam pada 24 jam
pertama dan tidak boleh terlalu lama setiap suksion, biasanya 10-15detik.
Bila lama penderita bisa sesak atau hipoksia atau cardiac arrest dan
lakukanlah berkali-kali sampai bersih.
3. Anak: kanul dibersihkan setiap hari kemudian pasang kembali.
Pengangkatan kanul dilakukan secepatnya, atau dengan indikasi berikut:
Tutup lubang trakeostomi selama 3 menit, penderita tidak sesak.
Dalam 25 jam tidak ada keluhan sesak bila lubang trakeostomi ditutup
waktu tidur, makan dan bekerja.
Penderita sudah dapat bersuara.
Komplikasi trakeostomi:

- Waktu operasi: Perdarahan, lesi organ sekitarnya, apnea dan shock.
- Pasca operasi:Infeksi, sumbatan, kanul lepas, erosi ujung kanul atau desakan
cuff pada pembuluh darah, fistel trakeokutan, sumbatan subglotis dan trakea,
disfagia,granulasi.
Teknik trakeostomi:
1. Penderita tidur telentang dengan kaki lebih rendah 30˚ untuk
menurunkan tekanan vena di daerah leher. Punggung diberi ganjalan
sehingga terjadi ekstensi. Leher harus lurus, tidak boleh laterofleksi
atau rotasi.
2. Dilakukan desinfektan daerah operasi dengan betadin atau alkohol.
3. Anestesi lokal subkutan, prokain 2% atau silokain dicampur
denganepinefrin atau adrenalin 1/100.000. Anestesi lokal atau infiltrasi
ini tetapdiberikan meskipun trakeostomi dilakukan secara anestesi
umum
4. Dilakukan insisi,
Insisi vertikal: dimulai dari batas bawah krikoid sampai fossa
suprasternum,insisi ini lebih mudah dan alir sekret lebih mudah
Insisi horizontal: dilakukan setinggi pertengahan krikoid dan
fossa sternum,membentang antara kedua tepi depan dan medial
m.sternokleidomastoid, panjang irisan 4-5 cm.Irisan mulai dari
kulit, subkutis, platisma sampai fasia colli superfisialsecara
tumpul. Bila tampak ismus, maka ismus disisikan ke atas atau
ke bawah. Bila mengalami kesukaran dan tidak memungkinkan,
potong saja.
5. Bila sudah tampak trakea maka difiksasi dengan kain tajam. Kemudian
suntikkan anestesi lokal kedalam trakea sehingga tidak timbul batuk
pada waktu memasang kanul.
6. Stoma dibuat pada cincin trakea 2-3 bagian depan, setelah dipastikan
trakea yaitu dengan menusukkan jarum suntik dan letakkan benang
kapas tersebut.Kemudian kanul dimasukkan dengan bantuan dilator.
7. Kanul difksasi dengan pita melingkar leher, jahitan kulit sebaiknya
jahitan longgar agar udara ekspirasi tidak masuk ke jaringan dibawah
kulit.

Gambar. Teknik Trakeostomi
Kontrol Perdarahan
1. A. Maksilaris
Perdarahan yang hebat dapat terjadi dan harus ditangani segera. Misalnya,
perdarahan sentral dari a.maksilaris. Pada fraktur muka, rupture dari arteri di
bagian pterigopalatina dapat menyebabkan perdarahan yang hebat. Darah dapat
terlihat mengalir dari sinus maksilaris, hidung, rongga mulut, dan tenggorok.
Pasien bahkan dapat mengalami syok hemoragik atau syok hipovolemik karena
kehilangan darah yang banyak. Penatalaksanaan perdarahan dari a.maksilaris
adalah dengan menekan atau kompresi rahang atas arah ke skullbase dalam arah
dosokranial dan pada waktu yang bersamaan memasukkan tampon intranasal ke
dalam hidung. Pada pasien yang tidak sadarkan diri, risiko aspirasi sangat besar,
karena itu sebaiknya tindakan ini dilakukan setelah dilakukan pembiusan total
dengan pemasangan endotrakeal tube.
2. A. Karotis
Perdarahan dari a.karotis di dasar tengkorak dapat berakibat fatal. Untuk
menghentikan perdarahan dapat dicoba dengan pemasangan tampon Belloq.
Walaupun dalam kebanyakan kasus umunya tidak dapat banyak menolong,

sehingga perdarahan dari a.karotis di dasar tengkorak ini umumnya dapat berakibat
fatal.
3. A. Etmoidalis Anterior dan Posterior
Perdarahan juga dapat terjadi dari a. etmoidalis anterior dan posterior.
Umumnya perdarahan ini dapat terkontrol dengan pemasangan tampon di hidung.
Dapat juga terjadi perdarahan infraorbital yang ditandai dengan hiposphagma
dengan kemosis dan protusio bulbi. Jika hal ini terjadi perlu dilakukan dekompresi
orbita lewat akses lateral kantotomi.
4. A. Temporalis, A. Facialis, A. Lingualis
Selain dari a.maksilaris, perdarahan juga dapat timbul dari cabang A.karotis
eksterna yang lain seperti dari a.temporalis, a.fasialis, dan a.lingualis. Perdarahan
dari arteri ini biasanya tidak sehebat perdarahan dari a.maksilaris. Perdarahan
dapat dikontrol dengan kompresi dan koagulasi.
Kegawatdaruratan yang Membutuhkan Pembedahan dan yang Dapat
Terjadi Pada Saat Pembedahan
Trauma jaringan lunak
Secara umum, pada semua luka atau trauma jaringan lunak perlu dilakukan
interverensi bedah untuk merekontruksi dan mengembalikan fungsi jaringan ke
keadaan normal, kecuali pada trauma jaringan lunak tingkat I.
Semua perawatan pada jaringan lunak perlu dilakukan dalam keadaan steril.
Prinsip dasarnya adalah membersihkan daerah luka, misalnya dengan H2O2. Jika
terdapat fraktur tulang, maka jika memungkinkan fraktur tulang harus diterapi
terlebih dahulu baru kemudian menutup jaringan lunak (prinsip merawat dari
bagian dalam keluar).
Tabel . Klasifikasi trauma jaringan lunak berdasarkan kedalaman luka.
Tingkatan Kedalaman
I Hanya pada bagian permukaan epidermis dan dermis
tanpa melibatkan stratum basalis

II Terputusnya lapisan epidermis dan dermis
III Terputusnya lapisan epidermis, dermis, dan jaringan
lunak subkutan
IV Terputusnya lapisan epidemis, dermis, jaringan lunak
subkutan, dan juga melibatkan struktur tulang
dibawahnya
Tidak seperti pada prinsip bedah umum bahwa penutupan luka secara primer
untuk menghindari infeksi dan proliferasi bakteri dapat dilakukan jika waktu
trauma kurang dari 6-8 jam, pada luka bagian mulut dan muka penutupan atau
penjahitan luka secara primer masih dapat dilakukan pada luka yang terjadi
maksimal 48 jam.
Pada trauma jaringan lunak dengan defek atau kehilangan jaringan lunak, dapat
dilakukan rekontruksi primer dengan menggunakan flap regional dan pada kasus-
kasus yang berat dapat dilakukan transplantasi jaringan dengan free flap transfer
secara mikrosurgeri.
Syok Hipovolemik
Syok hipovolemik merupakan kondisi medis atau bedah dimana terjadi
kehilangan cairan dengan cepat yang berakhir pada kegagalan beberapa organ,
disebabkan oleh volume sirkulasi yang tidak adekuat dan berakibat pada perfusi
yang tidak adekuat. Paling sering, syok hipovolemik merupakan akibat kehilangan
darah yang cepat (syok hemoragik).
Syok hipovolemik dapat disebabkan oleh kehilangan volume massive yang
disebabkan oleh: perdarahan gastro intestinal, internal dan eksternal hemoragi, atau
kondisi yang menurunkan volume sirkulasi intravascular atau cairan tubuh lain,
intestinal obstruction, peritonitis, acute pancreatitis, ascites, dehidrasi dari
excessive perspiration, diare berat atau muntah, diabetes insipidus, diuresis, atau
intake cairan yang tidak adekuat.
Kemungkinan besar yang dapat mengancam nyawa pada syok hipovolemik
berasal dari penurunan volume darah intravascular, yang menyebabkan penurunan
cardiac output dan tidak adekuatnya perfusi jaringan. Kemudian jaringan yang

anoxia mendorong perubahan metabolisme dalam sel berubah dari aerob menjadi
anaerob. Hal ini menyebabkan akumulasi asam laktat yangmenyebabkan asidosis
metabolik.
Ketika mekanisme kompensasi gagal, syok hipovolemik terjadi pada rangkaian
keadaan di bawah ini:
1. Penurunan volume cairan intravascular
2. Pengurangan venous return, yang menyebabkan penurunan preload dan
stroke volume
3. Penurunan cardiac output
4. Penurunan Mean Arterial Pressure (MAP)
5. Kerusakan perfusi jaringan
6. Penurunan oksigen dan pengiriman nutrisi ke sel
7. Kegagalan multisistem organ
Penatalaksanaan Syok Hipovolemik
Tujuan utama dalam mengatasi syok hipovolemik adalah
a. memulihkan volume intravascular untuk membalik urutan peristiwa
sehingga tidak mengarah pada perfusi jaringan yang tidak adekuat
b. meredistribusi volume cairan
c. memperbaiki penyebab yang mendasari kehilangan cairan secepat
mungkin.
Akibat perdarahan, untuk menangani syok hipovolemik, dilakukan:
Menghentikan sumber perdarahan
Posisikan badan lebih rendah daripada kaki
Jika memungkinkan observasi pasien segera di unit intensif
Pemberian O2 (4-8 L/menit) atau lakukan intubasi
Pemasangan akses iv secepatnya
Pemeriksaan laboratorium darah
Penggantian cairan tubuh, misalnya dengan NaCl 0,9% 1000-2000nml
atau lebih.
Transfusi darah

Fresh frozen plasma (FFP) diberikan jika Quick <40%, INR>2,0, PTT
>60 detik atau fibrinogen <75mg/dl
Jika diperlukan dapat dilakukan pemasangan kateter vena sentral
Syok hipotermia
Syok adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh gangguan hantaran oksigen
ke sel tubuh, atau gangguan ambilan dan utilisasi oksigen secara normal.
Perdarahan dengan penurunan curah jantung merupakan penyebab tersering syok
pada pasien trauma. Trauma dan perdarahan dengan hipoperfusi jaringan
mengganggu termoregulasi sehingga menyebabkan hipotermia. Beberapa faktor
yang menyebabkan hipotermia pada pasien trauma adalah paparan yang
berkepanjangan terhadap lingkungan dingin dan pemberian cairan intravena yang
dingin.
Penyebab hipotermia pada pasien trauma adalah:
Kegagalan termoregulasi dan penurunan produksi panas tubuh, diakibatkan
oleh:
o Cedera setempat
o Cedera susunan saraf pusat
o Syok (hipoperfusi jaringan)
o Umur yang ekstrim (terlalu tua atau muda)
o Anestesia umum atau blok neuroaksial
o Kondisi pengobatan seperti pada penderita diabetes mellitus dan gagal
jantung
o Pengaruh obat-obatan dan senyawa lain seperti alkohol dan antidepresan
trisiklik.
o Meningkatnya kehilangan panas tubuh

o Paparan terhadap lingkungan dingin
o Cairan intravena atau darah transfusi yang dingin
o Luka bakar
o Anestesia umum atau blok neuroaksial
Hipotermia yang tidak disengaja pada korban trauma merupakan masalah yang
sering terjadi pada awal fase resusitasi dan sering sering terabaikan. Tindakan-
tindakan sederhana sebenarnya dapat mencegah terjadinya hipotermia pada pasien
trauma. Metode menghangatkan pasien trauma yang hipotermia meliputi baik
penghangatan eksternal pasif, penghangatan eksternal aktif, dan penghangatan
internal aktif. Penghangatan eksternal pasif dilakukan dengan memisahkan pasien
dari lingkungan yang dingin dan melakukan penutupan tubuh pasien dari paparan
dingin. Penghangatan eksternal aktif dapat dilakukan dengan pemberian air atau
udara hangat disekitar tubuh pasien, juga selimut atau benda hangat lainnya.
Sedangkan penghangatan internal aktif dapat dilakukan dengan memberikan
inhalasi udara panas, pemberian cairan infus yang dihangatkan, bilas lambung
dengan air hangat, irigasi kandung kemih atau mediastinum dengan cairan hangat.
Penatalaksanaan hipotermia pada pasien trauma seharusnya dimulai dengan
pencegahan kehilangan panas tubuh. Resusitasi cairan dapat menyebabkan
penurunan suhu tubuh, sehingga diperlukan alat penghangat cairan sebelum
dimasukkan ke dalam tubuh. Dari berbagai modalitas terapi non-invasif,
penghangatan konveksi efektif dalam mengembalikan suhu inti tubuh, walaupun
panas radiasi mungkin lebih mudah diberikan pada pasien dengan trauma multipel.
Tehnik penghangatan suhu aktif seperti CAVR meningkatkan suhu inti 1,5oC
sampai 2,5oC/jam, dan dapat mencegah kematian pada pasien trauma yang
mengalami hipotermia.
Trauma jaringan keras (Fraktur maksilofasial)

Umumnya terjadi karena trauma dengan kecepatan tinggi seperti kecelakaan
lalulintas dan kecelakaan lainnya. Tindakan yang terutama adalah membebaskan
jalan nafas. Bebaskan semua trauma pada pasien sepanjang jalan nafas dengan
pedoman ATLS. Masalah lain yang mengancam kehidupan seperti pendarahan
intracranial, pendarahan hebat dari organ lain dan kerusakan tulang leher harus
segera ditangani. Dalam pengamatan selanjutnya, perhatikan robekan pada kepala
dan adanya kebocoran cairan serebrospinal.
Pada penatalaksanaan fraktur, walaupun terjadi kerusakan wajah yang parah,
tetapi hal tersebut bukan merupakan prioritas yang utama. Namun serpihan seperti
gigi yang patah, darah, atau air liur harus dibersihkan dari mulut. Dan diperlukan
pembebasan jalan nafas orofaringeal.
Fraktur Mandibula
Pada kasus fraktur ini biasanya tidak berhubungan dengan luka atau
pendarahan lain yang serius. Fraktur sederhana yang tidak bergeser dapat dirawat
secara konservatif dengan diet lunak apabila gigi tidak rusak. Lain halnya saat
sympysis mengalami remuk, lidah dapat terdorong ke belakang dan menyumbat
jalan nafas, maka hal ini perlu dicegah. Jika fragmen bergeser, nyeri cenderung
terjadi maka penatalaksanaan yang baik adalah fiksasi dini. Umumnya fraktur
dapat ditangani dengan pembedahan dan fiksasi dengan mini plate.
Fraktur tengkorak bagian sepertiga tengah atas.
Fraktus ini biasanya ditimbulkan oleh trauma yang parah seperti kecelakaan
lalu lintas. Klasifikasinya menurut garis fraktur Le Fort (Fraktur horizontal pada
bilateral maksila).
Klasifikasi Fraktur Le Fort :
Le Fort I : bagian bawah dasar hidung segmentasi/horizontal dari processus
alveolaris (pembengkakan bibir bagian bawah)
Le Fort II : unilateral atau bilateral maksila (subzygomaticus),
menyebabkan pembengkakan wajah yang masif (ballooning) dan (Panda
Facies)

Le Fort III : Seluruh maksila (suprazygomatic) dan satu atau lebih tulang
wajah terpisah dari kerangka craniofacial (terjadi pembengkakan wajah
massif dan kebocoran cairan serebrospinal melalui hidung).
Pada klasifikasi Le Fort ini, mungkin terdapat pula terjadi penyumbatan jalan
nafas, cedera kepala, cedera dada, robekan organ visceralis, fraktur tulang
belakang dan tulang panjang. Sebagian besar fraktur sepertiga tengah dirawat
dengan pembedahan dan fiksasi dengan mini plate.
Jadi, prioritas utama penanganan pasien dengan fraktur maxillofacial adalah
membebaskan jalan nafasnya, jika pembebasan jalan nafas sudah dilakukan dengan
tepat barulah tindakan-tindakan selanjutnya dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA
1. Budihardja, AS, dkk. 2011. Trauma Oral & Maksilofasial. Jakarta: EGC.
2. Pedersen, Gordon W. 1996. Buku Ajar Praktis Bedah Mulut. Jakarta: EGC.
3. Juniper RP, dkk. 1996. Kedaruratan dalam praktik dokter gigi. Jakarta: EGC
4. Dewi, Enita, dkk. 2010. Kegawatdaruratan syok hipovolemik. Berita Ilmu
Keperawatan ISSN 19792697, Vol. 2. No. 2 93-96