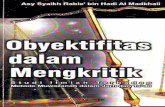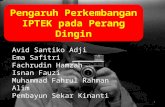0856 4347 4222, Benih Sayuran Unggul, Bibit Sayuran Murah, Jual Benih Cabe Rawit Unggul
unggul dalam iptek
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of unggul dalam iptek
UNGGUL DALAM IPTEK KOKOH DALAM IMTAQ
LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGARUH PEMBERIAN EMLA TERHADAP TINGKAT NYERI
ANAK USIA PRASEKOLAH YANG DILAKUKAN PEMASANGAN INFUS
DI RUANG ANAK GEDUNG A RSCM JAKARTA
Oleh :
SUNARDI
2011727077
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN 2013
iv
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Riset Keperawatan, Tahun 2013
SUNARDI
“ Pengaruh Pemberian EMLA Terhadap Tingkat Nyeri Anak Usia
Prasekolah Yang Dilakukan Pemasangan Infus Di Ruang Anak
Gedung A RSCM Jakarta ”.
VII BAB + 72 Halaman + 6 Tabel + 7 Lampiran
ABSTRAK
Perawatan atraumatik pada prosedur invasif telah direkomendasikan, diantaranya dengan pemberian EMLA.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian EMLA terhadap tingkat nyeri anak usia prasekolah yang dilakukan pemasangan infus. Design penelitian ini menggunakan studi quasi eksperimen dengan rancangan nonequivalent control group, after only design.Responden yang menjadi subyek penelitian ini adalah anak usia prasekolah yang dirawat di Ruang Anak Gedung A RSCM Jakarta .Dari 40 responden dibagi dua kelompok, 20 responden sebagai kelompok intervensi dan 20 responden sebagai kelompok kontrol. Terdapat perbedaan tingkat nyeri yang signifikan antara anak usia prasekolah yang diberikan EMLA dengan anak usia prasekolah yang tidak diberikan EMLA saat dilakukan pemasangan infus dengan p value 0, 00. Saran dari penelitian ini ditujukan kepada institusi pelayanan keperawatan dan profesi keperawatan hendaklah menerapkan management nyeri dalam tindakan pemasangan infus pada anak usia prasekolah.
Daftar Pustaka : 24 (2002-2009)
Kata Kunci : EMLA, tingkat nyeri, anak usia prasekolah.
v
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum WR.WB.
Dengan segala kerendahan hati, peneliti panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah
SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga
peneliti dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian dengan judul “ Pengaruh
pemberian EMLA terhadap tingkat nyeri anak usia prasekolah yang dilakukan
pemasangan infus di Ruang Anak Gedung A RSCM Jakarta “.Adapun penelitian ini
dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat pembuatan penelitian yang berkaitan
dengan mata ajaran riset keperawatan pada PSIK-FKK UMJ Jakarta.
Dalam penyusunan usulan penelitian ini, peneliti menyadari banyak mendapatkan
hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan dan bantuan serta dorongan dari
berbagai pihak, peneliti dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan tepat
waktu.Untuk itu pada kesempatan ini peneliti dengan tulus ikhlas menyampaikan
terima kasih yang tidak terhingga kepada :
1. Bapak Muhammad Hadi, SKM.MKep, selaku ketua program pendidikan PSIK-
FKK Universitas Muhammadiyah Jakarta dan selaku pembimbing II metodologi
riset keperawatan yang selalu memberikan petunjuk-petunjuk di dalam
menyelesaikan pembuatan penelitian ini.
2. Ibu Nyimas Heny Purwati,M.Kep.Sp.Kep.An, selaku pembimbing I metodologi
riset keperawatan yang memberikan pengarahan dan bimbingan dengan penuh
kesabaran dan juga sebagai penguji I.
3. Ibu Miciko Umida, SKp, Mbiomed, sebagai penguji II.
vi
4. Ibu Anita A, M.Kep.Sp.Kep.An, sebagai penguji III .
5. Istri dan kedua anakku tercinta yang selalu memberikan dukungan moril dan
materiil, dorongan semangat serta membantu di dalam penyelesaian penelitian
ini.
6. Direktur RSCM Jakarta yang telah memberikan ijin untuk mengikuti
pendidikan.
7. Supervisor Gedung A Lantai 1 Zona A RSCM, yang telah memberikan
dukungan dan membantu di dalam proses penelitian ini.
8. Teman-teman seangkatan di kampus UMJ serta teman-teman seprofesi di
ruangan kerja khususnya tempat peneliti bernaung keseharian kerja yang telah
memberikan dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan ini.
Akhir kata peneliti banyak terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu
dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.Dengan segala keterbatasan peneliti
menyadari bahwa dalam menyusun proposal penelitian ini jauh dari kesempurnaan,
untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi
kesempurnaan proposal penelitian ini.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Jakarta, Februari 2013
Peneliti
vi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i
LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................................ ii
LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................. iii
ABSTRAK ........................................................................................................... iv
KATA PENGANTAR .......................................................................................... v
DAFTAR ISI ......................................................................................................... vii
DAFTAR TABEL ................................................................................................. ix
DAFTAR SKEMA ................................................................................................ x
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ......................................................................................... 1
B. Pertanyaan Penelitian ................................................................................ 6
C. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 6
D. Manfaat Penelitian .................................................................................... 7
BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN
A. Anak Usia Prasekolah ............................................................................... 8
B. Hospitalisasi ............................................................................................... 9
C. Nyeri .......................................................................................................... 12
D. EMLA ........................................................................................................ 27
BAB III. KERANGKA KONSEP,HIPOTESIS DAN DEFINISI OPERASIONAL
A. Kerangka Konsep........................................................................................ 33
B. Hipotesis Penelitian..................................................................................... 35
C. Definisi Operasional ................................................................................... 36
vii
BAB IV. METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian....................................................................................... 39
B. Populasi dan Sampel.................................................................................. 40
C. Tempat Penelitian....................................................................................... 43
D. Waktu Penelitian........................................................................................ 43
E. Etika Penelitian.......................................................................................... 44
F. Alat Penelitian............................................................................................ 46
G. Prosedur Pengumpulan Data...................................................................... 47
H. Pengolahan Data......................................................................................... 51
I. Analisa Data ............................................................................................... 52
BAB V HASIL PENELITIAN
A. Analisa Univariat ........................................................................................ 54
B. Analisa Bivariat ......................................................................................... 58
BAB VI PEMBAHASAN
A. Keterbatasan Penelitian .............................................................................. 61
B. Analisa Univariat ........................................................................................ 61
C. Analisa Bivariat .......................................................................................... 67
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ................................................................................................ 70
B. Saran .................................................................................................. 71
DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................
LAMPIRAN ...........................................................................................................
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel, definisi operasional, cara ukur, hasil ukur
dan skala ukur................................................................................. 36
Tabel 4.1 Uji statistik ..................................................................................... 53
Tabel 5.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Kehadiran Keluarga,
Ketakutan anak, dan Pengalaman di Infus Sebelumnya, Februari 2013
........................................................................................................ 55
Tabel 5.2 Distribusi Tingkat Nyeri Dirasakan Responden Saat dilakukan
Pemasangan Infus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Februari 2013
....................................................................................................... 57
Tabel 5.3 Rata-rata Skor Nyeri Anak Usia Prasekolah yang dilakukanPemasangan
Infus Terhadap Pemberian EMLA di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo,
Februari 2013 ............................................................................... 58
Tabel 5.4 Distribusi Responden Menurut Tingkat nyeri Anak Usia Prasekolah yang
Dilakukan Pemasangan Infus Di Rumah Sakit CiptoMangunkusumo,
Februari 2013 ............................................................................. 59
x
DAFTAR SKEMA
Skema 3.1 Kerangka konsep penelitian ............................................................ 34
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Anak adalah tunas bangsa,potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan
bangsa. Anak juga memiliki peran strategi dan mempunyai ciri serta sifat khusus
yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa mendatang.
Sehingga anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia
serta mendapatkan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak (Undang-
Undang Perlindungan Anak, 2002).
Apabila anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit (mengalami hospitalisasi) akan
menimbulkan stress besar bagi anak dan keluarga serta dapat menyebabkan berbagai
perubahan fisiologis dan mental. Stress menyebabkan ketidaknyamanan pada anak
dan keluarga dan menuntut anak dan keluarga menggunakan koping untuk mengatasi
masalah. Stress pada anak akibat hospitalisasi disebabkan oleh berbagai faktor
seperti perpisahan, nyeri, rasa takut dan tidak berdaya sehingga mempengaruhi
kontrol dirinya. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh : usia perkembangan,
pengalaman sakit yang lalu, perpisahan, sistem pendukung, koping yang digunakan
dan keseriusan penyakitnya. Seringkali anak dan keluarga memandang penyakit dan
tindakan pengobatan sebagai ancaman (Wong, 2006).
2
Keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit pada anak dapat menimbulkan stress yang
disebabkan oleh karena anak tidak memahami mengapa harus dirawat, lingkungan
yang asing, prosedur tindakan yang menyakitkan serta terpisah dengan keluarga
(Supartini, 2004). Anak mengalami masa yang sulit karena tidak terpenuhi
kebutuhannya seperti halnya di rumah. Hal ini dapat berdampak negatif bagi
perkembangan anak, misalnya anak menjadi menarik diri, regresi. Anak seringkali
merasa takut bila menghadapi sesuatu yang dapat mengancam integritas dan
tubuhnya.
Menurut Wong (2006) disebutkan bahwa, konsep sakit dimulai selama periode
prasekolah dan dipengaruhi oleh kemampuan kognitif pada tahap praoperasional.
Anak prasekolah sulit membedakan antara dirinya sendiri dan dunia luar. Pemikiran
difokuskan pada kejadian eksternal yang dirasakan, dan kualitas dibuat berdasarkan
kedekatan antara dua kejadian. Konflik psikoseksual anak pada kelompok usia ini
membuatnya sangat rentan terhadap ancaman cedera tubuh, prosedur intrusif, baik
yang menimbulkan nyeri maupun yang tidak, merupakan ancaman bagi anak
prasekolah yang konsep integritas tubuhnya belum berkembang baik. Anak
prasekolah dapat bereaksi terhadap injeksi sama khawatirnya dengan nyeri saat
jarum dicabut, takut intrusif atau fungsi pada tubuh tidak akan menutup kembali dan
“ isi tubuh “ akan bocor keluar.
Reaksi terhadap nyeri pada anak usia prasekolah cenderung sama dengan yang
terlihat pada masa toddler, meskipun beberapa perbedaan menjadi jelas. Misalnya,
respon anak usia prasekolah terhadap intervensi persiapan dalam hal penjelasan dan
3
distraksi lebih baik dibandingkan dengan respon anak yang lebih kecil. Agresi fisik
dan verbal lebih spesifik dan mengarah pada tujuan. Anak usia prasekolah dapat
menunjukkan letak nyeri yang dirasakannya dan dapat menggunakan skala nyeri
dengan tepat (Hockenberry, 2007).
Nyeri yang didapat terkait dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial, atau
menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan. Penatalaksanaan nyeri yang efektif
membutuhkan profesional kesehatan yang mau mencoba berbagai intervensi untuk
memperoleh hasil yang optimum. Metode pengurangan nyeri dapat dikelompokkan
menjadi dua kategori yaitu nonfarmakologi dan farmakologi. Sejumlah teknik
nonfarmakologi diantaranya relaksasi, distraksi, memberikan strategik koping yang
dapat membantu mengurangi persepsi nyeri, membuat nyeri lebih dapat ditoleransi,
menurunkan kecemasan dan meningkatkan efektivitas analgesik. Pengurangan nyeri
merupakan kebutuhan dasar dan hak dari semua anak. Menurut International
Association for Study of Pain (IASP), nyeri adalah sensori subyektif dan emosional
yang tidak menyenangkan.
Respon lain dari hospitalisasi yaitu menangis keras dan tidak kooperatif dapat
ditampilkan anak usia prasekolah akibat menjalani suatu prosedur yang
menimbulkan nyeri bahkan kadang anak menolak dilakukan suatu prosedur dan tetap
melekat pada orang tuanya. Fenomena yang ada, anak akan cenderung menangis dan
meronta kesakitan selama prosedur invasif dilakukan, menurut salah satu perawat
yang berdinas di Ruang Anak Gedung A RSCM Jakarta mengatakan bahwa
meskipun teknik distraksi dengan pemberian bermain dan pendampingan orang tua
4
sudah dilakukan selama prosedur invasif tetapi hampir 80 % anak usia prasekolah
yang dilakukan tindakan invasif (injeksi dan pemasangan infus) masih menunjukkan
respon nyeri dengan menangis, meronta dan merasa kesakitan, sedangkan yang
lainnya ada yang berespon dengan menangis tetapi hanya sebentar. Keadaan seperti
ini akan membuat perawat mengalami kesulitan dalam melaksanakan suatu prosedur
invasif. Tindakan invasif merupakan suatu hal yang esensial dalam mendiagnosis
dan mengobati anak yang dirawat di rumah sakit. Prosedur pemasangan infus
mungkin akan dialami anak secara berulang dan hal seperti ini cenderung membuat
anak merasa trauma, keadaan ini bertentangan dengan prinsip perawatan atraumatik
pada anak.
Perawatan atraumatik merupakan perawatan terapeutik yang diberikan oleh tenaga
kesehatan dalam tatanan pelayanan kesehatan anak, melalui penggunaan tindakan
yang dapat mengurangi distres fisik dan distres psikologis yang dialami anak dan
orang tuanya. Perawatan atraumatik memperhatikan pada apa, siapa, dimana,
mengapa dan bagaimana prosedur dilakukan pada anak dengan tujuan mencegah dan
mengurangi stres fisik dan psikologis .
Penerapan perawatan atraumatik pada anak saat prosedur invasif dilakukan telah
diidentifikasi dalam beberapa literatur. Tindakan seperti pendampingan orang tua,
bermain dan pemberian analgesik sebelum prosedur dapat mengurangi stres fisik dan
psikologis pada anak. Prinsip perawatan atraumatik untuk mengontrol nyeri
prosedural injeksi antara lain dengan menggunakan jarum berukuran kecil, distraksi
dan pemberian krim EMLA (Eutectic Mixture of Local Anesthetics). Krim EMLA
5
adalah suatu krim anestesi topikal yang telah diketahui keefektifannya dalam
menurunkan intensitas nyeri. Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2002 di
Amerika melaporkan bahwa pemakaian EMLA sebelum tindakan injeksi imunisasi
dapat menurunkan intensitas nyeri yang ada.
Berdasarkan data medical rekod, jumlah pasien di Ruang Anak Gedung A RSCM
Jakarta yang dirawat selama periode Januari sampai dengan Oktober 2012
sebanyak 1038 anak. Dimana anak usia prasekolah yang dirawat sebanyak 276 anak
(26,78 %).
Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap 5 anak prasekolah yang dirawat
menunjukkan perilaku kecemasan/ketakutan pada prosedur tindakan yang akan
dilakukan terutama tindakan infasif, anak menunjukkan perilaku menangis,
menjerit, menolak perawat dan tidak kooperatif, bahkan mendorong orang/petugas
yang akan melakukan prosedur agar menjauh atau anak dapat menganiaya perawat
secara verbal dengan mengatakan “ pergi dari sini “ atau “ saya benci kamu “.
Kondisi ini terjadi terutama pada anak yang baru pertama kali dirawat dan anak
yang mempunyai pengalaman dirawat tidak menyenangkan pada rawatan
sebelumnya.
Atraumatic Care merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kondisi anak yang
demikian, salah satunya dengan menggunakan pemberian EMLA dalam
melaksanakan intervensi keperawatan yang diberikan kepada anak. Hal ini sudah
mulai dilakukan di Indonesia, khususnya di Ruang Anak Gedung A RSCM Jakarta,
pemberian EMLA pada prosedur invasif sudah mulai diterapkan. Pendekatan
6
melalui beberapa teknik dapat dilakukan untuk mengurangi respon nyeri pada anak
saat prosedur invasif dilakukan. Keadaan ini yang menjadi fokus perhatian peneliti
untuk meneliti tentang pengaruh pemberian EMLA terhadap tingkat nyeri anak usia
prasekolah yang dilakukan prosedur invasif ( pemasangan infus).
B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian di atas membuat peneliti tertarik untuk mengetahui “
Bagaimana pengaruh pemberian EMLA terhadap tingkat nyeri anak usia prasekolah
yang dilakukan pemasangan infus di Ruang Anak Gedung A RSCM Jakarta ?“
C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan umum
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian EMLA terhadap
tingkat nyeri anak usia prasekolah yang dilakukan pemasangan infus di Ruang
Anak Gedung A RSCM Jakarta.
2. Tujuan khusus
a. Teridentifikasinya gambaran karakteristik anak usia prasekolah yang
dilakukan pemasangan infus di Ruang Anak Gedung A RSCM Jakarta.
b. Teridentifikasinya tingkat nyeri anak usia prasekolah yang dilakukan
pemasangan infus baik pada kelompok kontrol maupun kelompok intervensi
di Ruang Anak Gedung A RSCM Jakarta.
7
c. Teridentifikasinya tingkat nyeri anak usia prasekolah yang dilakukan
pemasangan infus dengan diberikan EMLA di Ruang Anak Gedung A
RSCM Jakarta.
d. Ada pengaruh pemberian EMLA terhadap tingkat nyeri anak usia prasekolah
yang dilakukan pemasangan infus di Ruang Anak Gedung A RSCM Jakarta.
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi institusi pelayanan keperawatan
Memberikan masukan pada institusi perawatan tentang perlu dikembangkannya
prinsip perawatan atraumatik selama tindakan invasif ( pemasangan infus).
2. Bagi profesi keperawatan
Hasil penelitian ini akan memberikan dampak pada perkembangan ilmu
keperawatan,khususnya tentang pengaruh pemberian EMLA terhadap tingkat
nyeri anak usia prasekolah yang dilakukan pemasangan infus.
3. Bagi komunitas penelitian
Menjadi dasar bagi pengembangan penelitian yang lebih lanjut.
8
BAB II
STUDI KEPUSTAKAAN
A. Anak Usia Prasekolah
Anak prasekolah adalah anak yang berusia antara 3 sampai 6 tahun (Hidayat, 2004).
Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah masa balita di dalamnya
termasuk masa prasekolah. Karena pada masa ini sebagai dasar yang akan
mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Pada usia ini anak
mulai mengembangkan kemampuan fisik dan personality. Karakteristik
perkembangan fisik pada anak usia prasekolah ditandai dengan maturnya sistem
tubuh, berkembangnya motorik kasar dan motorik halus. Fungsi-fungsi tubuhnya
sudah terkontrol, pengalaman karena perpisahan yang singkat dan sangat lama,
kemampuan untuk berinteraksi secara kooperatif dengan anak lain dan orang
dewasa. Perkembangan motorik,bahasa dan personal social anak usia prasekolah
mulai berkembang. Anak belajar tentang norma, kontrol diri dan berpikir imaginasi.
Kesadaran diri anak usia prasekolah meningkat dan anak mulai tidak tergantung
serta mengembangkan diri (Hockenberry, 2007).
Apabila ditinjau dari perkembangan sosial anak usia prasekolah, kelompok usia ini
umumnya memiliki toleransi yang lebih baik dalam hal perpisahan dengan orang tua
dibandingkan dengan anak usia toddler. Anak usia prasekolah mampu berhubungan
secara mudah dengan orang asing dan lebih toleran terhadap perpisahan dengan
9
orang tua dengan hanya sedikit atau tanpa protes. Namun demikian, anak masih
membutuhkan perlindungan, pengamanan, bimbingan dan persetujuan dari orang
tua, terutama ketika memasuki dunia sekolah.
Perpisahan yang panjang dengan orang tua merupakan hal yang sulit bagi anak usia
prasekolah, akan tetapi dapat berespon baik apabila mendapat penjelasan atau
persiapan, misalnya perpisahan yang disebabkan oleh penyakit atau hospitalisasi
(Hockenberry, 2007). Anak usia prasekolah dapat mengatasi perubahan rutinitas
harian lebih baik dari toddler, tetapi bisa lebih mengembangkan ketakutan imajiner.
Kelompok usia ini mampu bekerja melewati beberapa ketakutan yang belum
terpecahkan, fantasi, dan kebimbangan atau kegelisahan selama bermain.
B. Hospitalisasi
Hospitalisasi adalah suatu proses karena suatu alasan darurat atau berencana
mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit menjalani terapi dan perawatan.
Selama proses tersebut anak dan juga orang tua akan mengalami kebiasaan dan
lingkungan yang asing (Supartini, 2004). Reaksi anak prasekolah terhadap
perpisahan ditunjukkan dengan menolak makan, sering bertanya, menangis dan
tidak kooperatif terhadap petugas kesehatan. Perawatan dan rumah sakit sering
dipersepsikan usia prasekolah sebagai hukuman sehingga anak akan merasakan
malu, bersalah atau takut. Ketakutan anak terhadap perlakuan muncul karena anak
menganggap tindakan-tindakan prosedur mengancam integritas tubuhnya
(Supartini, 2004).
10
Peran perawat dalam meminimalkan stress akibat hospitalisasi pada anak dan
keluarga sangat penting. Perawat perlu memberikan dukungan bagi anak dan
keluarga sebelum, selama dan setelah hospitalisasi untuk meminimalkan stress
akibat hospitalisasi. Selama persiapan hospitalisasi, anak dan keluarga
diperkenalkan pada ruang rawat. Selama hospitalisasi, perawat bekerja sama dengan
orang tua untuk menggunakan berbagai cara dalam meningkatkan koping dan
adaptasi,atau persiapan anak apabila memerlukan tindakan ataupun pembedahan.
Perawat berperan sebagai perantara apabila anak dirawat dalam jangka waktu yang
lama. Perawat juga bekerja sama dengan keluarga untuk mempersiapkan perawatan
anak selama di rumah atau apabila perlu penanganan lanjut di fasilitas rehabilitasi
(Hockenberry, 2007).
Perawatan di rumah sakit membuat anak kehilangan kontrol terhadap dirinya dan
mengharuskan adanya pembatasan aktivitas, sehingga anak merasa kehilangan
kekuatan dirinya. Keterbatasan yang dialami anak menimbulkan ketakutan dan
perhatian. Anak selalu ingin tahu tindakan - tindakan yang diterimanya dari rumah
sakit, sehingga mempengaruhi reaksi terhadap hospitalisasi tersebut. Hal ini
menunjukkan bahwa anak membutuhkan informasi sesuai kebutuhan dan
pandangannya terhadap rencana serta pelayanan dan lingkungan rumah sakit yang
sesuai bagi anak (Supartini, 2004).
Anak usia prasekolah sulit membedakan antara dirinya sendiri dan dunia luar.
Kelompok usia ini memiliki pemahaman bahasa yang terbatas dan hanya dapat
melihat satu aspek dari suatu objek atau situasi pada satu waktu. Anak usia
11
prasekolah merasa fenomena nyata yang tidak berhubungan sebagai penyebab
penyakit. Takut terhadap cedera tubuh dan nyeri mengarah kepada rasa takut
terhadap mutilasi dan prosedur yang menyakitkan.
Cara berpikir magis menyebabkan anak usia prasekolah memandang penyakit
sebagai suatu hukuman dan perpisahan dengan orang tua sebagai kehilangan kasih
sayang. Bagi anak usia prasekolah, hospitalisasi merupakan pengalaman baru dan
sering membingungkan yang dapat membawa dampak negatif terhadap
perkembangan normal. Hospitalisasi membuat anak masuk dalam lingkungan yang
asing, dimana anak biasanya dipaksa untuk menerima prosedur yang menakutkan,
nyeri tubuh dan ketidaknyamanan ( Muscari, 2005 ).
Egosentris dan pemikiran magis anak usia prasekolah membatasi kemampuan anak
untuk memahami berbagai peristiwa, karena kelompok usia ini memandang semua
pengalaman dari sudut pandangnya sendiri (egosentris). Tanpa persiapan yang
adekuat terhadap lingkungan yang tidak dikenal atau pengalaman, penjelasan fantasi
anak usia prasekolah untuk peristiwa-peristiwa semacam itu biasanya berlebihan,
aneh dan menakutkan dari kejadian yang sebenarnya. Anak usia prasekolah
seringkali mempersepsikan perawatan di rumah sakit sebagai hukuman sehingga
anak akan merasa malu, bersalah dan takut (Hockenberry, 2007).
Takut akan cidera tubuh dan nyeri sering terjadi di antara anak-anak. Konflik
psikoseksual pada kelompok anak usia prasekolah membuatnya sangat rentan
terhadap ancaman cedera tubuh. Ketakutan anak terhadap perlukaan muncul karena
anak menganggap tindakan dan prosedur baik yang menimbulkan nyeri maupun
12
yang tidak, merupakan ancaman bagi integritas tubuhnya. Oleh karena itu, hal ini
menimbulkan reaksi agresif dengan marah dan berontak, ekspresi verbal dengan
mengucapkan kata-kata marah, tidak mau bekerja sama dengan perawat, dan
ketergantungan pada orang tua (Hockenberry, 2007).
C . Nyeri
a. Pengertian Nyeri
Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan yang tidak menyenangkan bersifat
sangat subjektif karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang dalam hal skala
atau tingkatannya, dan hanya orang tersebutlah yang dapat menjelaskan atau
mengevaluasi rasa nyeri yang dialaminya.Menurut Merskey dan Bogduk, nyeri
merupakan pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan yang
berhubungan dengan kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial, atau
dilukiskan dengan istilah seperti kerusakan (Craven & Himle, 2002).
Definisi lain mengatakan bahwa, nyeri sebagai suatu keadaan yang
mempengaruhi seseorang dan ekstensinya diketahui bila seseorang pernah
mengalaminya (Tamsuri, 2007). Sedangkan Mc Caffrey and Beebe menyatakan
bahwa nyeri adalah apa yang dikatakan oleh orang yang mengalaminya dan ada
bila orang yang mengalaminya mengatakan bahwa rasa itu ada (Betz & Sowden,
2002).
Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nyeri adalah suatu
keadaan ketidaknyamanan yang dapat timbul karena fenomena biopsikososial
13
yang komplek dan bersifat subjektif dan hanya orang yang menderitanya saja
yang dapat menjelaskan dan mengevaluasinya. Definisi ini tidak dengan
sendirinya berarti bahwa anak itu harus mengatakan bila sakit akan tetapi nyeri
dapat juga diekspresikan melalui menangis, pengutaraan, atau isyarat perilaku
(Betz & Sowden, 2002).
b. Fisiologi Nyeri
Nyeri adalah sebuah proses fisiologik kompleks yang dapat dibagi dalam
beberapa peristiwa neurokimiawi (terdapat 3 fase) :
1. Transduksi
Terjadi pada tempat dimulainya nyeri. Reseptor nyeri (nociceptor) di perifer
dirangsang oleh kejadian mekanik, termal, atau kimiawi. Rangsang ini
menimbulkan pelepasan substansi penghasil nyeri (seperti prostaglandin,
bradikinin, serotonin, histamin, substansi P) (Betz & Himle, 2002).
Stimulasi nyeri menyebabkan pergerakan ion – ion melewati membran sel.
Pengobatan nyeri dapat bekerja selama fase ini untuk membloking produksi
prostaglandin (contoh ibupprofin) atau menurunkan pergerakan ion natrium
melewati membran sel (contoh anestesi topikal) (Kozier, 2004).
2. Transmisi (transfer)
Fase transmisi terdiri dari tiga segmen, segmen pertama dari impuls berlanjut
saat masuk ke dalam kornu dorsalis dari medula spinalis melalui serat – serat
delta A yang besar dan bermielin tipis, serta serat – serat C yang kecil tanpa
14
mielin. Segmen kedua perpindahan impuls dari spinal cord dibawa melalui
jalur anterolateral ke thalamus dan pada segmen ketiga terjadi perpindahan
impuls dari thalamus ke korteks, di korteks inilah impuls diterima sebagai
nyeri (Kozier, 2004). Proses transmisi ini dapat diperjelas pada teori
gerbang kendali.
a. Teori gerbang kendali
Teori gerbang kendali / gate control theory mengemukakan bahwa
bahan substansia gelatinosa pada sum – sum belakang bekerja sebagai
mekanisme gerbang yang mengijinkan atau mengekang lewatnya
impuls nyeri. Gerbang dapat tertutup sehingga impuls nyeri tidak
sampai ke otak akan tetapi dapat pula terbuka yang memungkinkan
impuls nyeri sampai ke otak dan menimbulkan rasa nyeri, hal ini
tergantung dari stimulus yang ada (http://pain and why it hurt, 2005).
Tanpa adanya stimulasi, serat besar delta A dan serat kecil C berada
dalam keadaan diam dan inhibitor interneuron akan mengeblok impuls
sehingga nyeri tidak muncul di otak (gerbang dalam keadaan tertutup)
( http://pain and why it hurt, 2005))
Dengan stimulasi tidak nyeri (non nociceptor) seperti pemberian
anestesi topikal, masase dan distraksi akan mengaktifkan serat besar
delta A kemudian akan mengaktifkan inhibitor interneuron dengan
mengeblok impuls (gerbang dalam keadaan tertutup) sehingga impuls
tidak dapat atau hanya sedikit dihantarkan ke otak dan individu tidak
15
akan merasakan nyeri atau hanya sedikit merasa nyeri (http://pain and
why it hurt, 2005).
Adanya stimulasi nyeri (nociceptor) mengakibatkan serat kecil C
menjadi aktif dan kemudian serat kecil C tersebut akan mengaktifkan
hantaran impuls dan mengeblok inhibitor interneuron (gerbang dalam
keadaan terbuka) sehingga tidak dapat menahan impuls nyeri dan pada
akhirnya nyeri dapat dihantarkan ke otak dan individu akan merasakan
nyeri (http://pain and why it hurt, 2005).
b. Transmisi nyeri pada pemasangan infus
Nyeri pada prosedur pemasangan infus dapat dijelaskan bahwa
prosedur ini merupakan suatu tindakan memasukkan cairan atau obat
langsung ke dalam vena dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang
lama dengan menggunakan infus set. Penetrasi jarum ke dalam
jaringan pada tindakan ini akan menyebabkan terputusnya jaringan.
Hal ini merupakan salah satu stimulasi mekanik yang merangsang
nociceptor. Adanya rangsangan dapat menyebabkan terlepasnya
substansi penghasil nyeri dan mengaktifkan saraf berserat kecil C
(Betz & Sowden, 2002). Substansi penghasil nyeri akan melewati
membran sel dan dihantarkan berjalan sampai ke korteks (Kozier,
2004).
16
3. Modulasi ( menetralisir)
Nyeri terjadi pada otak di tingkat substansia grisea periakueduktus dan
medula oblongata, selain dalam kornu dorsalis dari medula spinalis, saat
opioid endogen (enkefalin) dilepaskan dalam jalur posterolateral, yaitu
dalam sebuah jalur eferen (Betz & Sowden, 2002). Tindakan distraksi pada
pemasangan infus bekerja pada jalur ini. Distraksi merupakan teknik
memfokuskan perhatian anak pada sesuatu selain pada nyeri (Smeltzer &
Bare, 2002). Diduga teknik distraksi dapat menurunkan persepsi nyeri
dengan menstimulasi produksi endorphin pada system kontrol eferen.
Endhorphin akan mengeblok impuls nyeri yang mengakibatkan stimulasi
nyeri lebih sedikit ditransmisikan ke otak (Smeltzer & Bare, 2002).
Pemfokusan perhatian dapat distimulasi melalui beberapa indera seperti
indera penglihatan, pendengaran, dan sentuhan .
Teknik distraksi pada anak usia prasekolah dapat berupa mendengarkan
musik, mendengarkan dongeng, menonton video, mencari gambar yang
tersamar, juga bisa dengan cara bermain (Betz & Sowden, 2002). Jenis
permainan yang cocok untuk anak usia prasekolah yang dirawat di rumah
sakit adalah dramatic play sedangkan jenis alat permainan yang sesuai
adalah permainan balok-balok besar, boneka dan buku cerita bergambar
(Supartini, 2004).
Teknik distraksi dengan membaca atau mendengarkan cerita bergambar
dapat mengalihkan perhatian klien dari rasa nyeri dan merangsang tubuh
17
mengeluarkan endhorpin yang dapat mengeblok impuls nyeri (http://pain
and why it hurt, 2005). Dengan mendengarkan cerita selain dapat
mengurangi rasa nyeri juga dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai
yang terkandung dalam cerita tersebut pada anak.
c. Nyeri pada Anak Usia Prasekolah
1. Karakteristik nyeri anak usia prasekolah
Sesuai dengan tingkat perkembangannya, anak prasekolah berada pada
tahapan praoperasional. Adapun karakteristik utamanya didasari oleh sifat
egosentrik. Bila karena suatu hal mereka merasakan nyeri, mereka akan
menyatakan bahwa nyeri merupakan pengalaman fisik yang konkret dan
berfikir untuk menghilangkan nyeri secara magis (Wong, 2003). Anak usia
ini memandang nyeri sebagai hukuman atas kesalahan dan mereka
cenderung membuat seseorang untuk bertanggung gugat atas nyerinya
sendiri dan dapat berespon dengan memukul orang lain (Wong, 2003).
2. Respon nyeri anak usia prasekolah
Nyeri yang dialami anak dapat menimbulkan berbagai respon, yaitu respon
fisiologis, respon neuroendokrin dan metabolik serta respon perilaku
(Kozier, 2004). Respon fisiologis akibat nyeri dapat berupa peningkatan
tekanan darah, peningkatan frekuensi denyut nadi dan peningkatan frekuensi
pernafasan (Kozier, 2004)). Pada respon neuroendokrin dan metabolik akan
terjadi proses katabolisme yang dapat menghasilkan energi yang dibutuhkan
18
oleh organ vital dan jaringan yang rusak, keadaan ini akan mengakibatkan
peningkatan metabolisme dan kebutuhan oksigen serta peningkatan gula
darah, asam lemak bebas, asam laktat dan keton. Respon ini muncul
tergantung pada derajat dan durasi dari kerusakan jaringan (Kozier, 2004).
Respon perilaku yang dapat ditunjukkan anak prasekolah terhadap nyeri
antara lain: respon menangis, respon ekspresi wajah dan respon gerakan
tubuh (Wong, 2003 ; Craven & Himle, 2002). a) Respon menangis, anak
cenderung akan marah, menangis keras dan berteriak, mengungkapkan
ekspresi verbal seperti “Aduh” atau “Sakit”, meminta penghentian prosedur
dan meminta dukungan emosional (Wong,2003; Kozier,2004). b) Ekspresi
wajah akan tampak meringis (Wong, 2003). c) Gerakan tubuh, anak dapat
menggerutukan gigi, memukul dahi, memukul lengan dan kaki, berusaha
menjauhkan stimulus sebelum stimulus ini diberikan, tidak kooperatif dan
perlu restrain fisik, melekat pada orang tua atau orang yang berarti, menjadi
gelisah dan peka terhadap nyeri lanjut (Wong, 2003).
Semua respon perilaku tersebut dapat terlihat pada antisipasi prosedur yang
dapat menimbulkan nyeri aktual seperti injeksi, tindakan pungsi vena, pungsi
jari dan pemasangan infus (Wong, 2003). Respon nyeri pada tiap anak tidak
selalu sama, karena respon nyeri seseorang dipengaruhi oleh beberapa
faktor.
19
d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Respon Nyeri
Nyeri yang dialami klien dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor
tersebut dapat meningkatkan atau menurunkan persepsi, toleransi dan sikap
respon terhadap nyeri. Faktor tersebut adalah: (Smeltzer & Bare, 2002).
1. Pengalaman masa lalu
Pengalaman nyeri yang dialami membuat individu merasa takut terhadap
peristiwa yang menyakitkan sehingga akan lebih sedikit mentoleransi
nyeri dan ingin nyerinya segera reda.
2. Kecemasan
Ansietas yang berhubungan dengan nyeri dapat meningkatkan persepsi
klien terhadap nyeri. Adanya perasaan cemas menyebabkan tubuh akan
berespon dengan mengadakan vasokontriksi yang dapat berakibat
terjadinya hipoksia, sedangkan keadaan hipoksia dapat meningkatkan
rasa nyeri yang ada.
3. Budaya
Orang dari budaya berbeda yang mengalami nyeri dengan intensitas sama
dapat berespon secara berbeda. Beberapa ras dan suku mempunyai
kecenderungan lebih mampu beradaptasi terhadap nyeri, misalnya
masyarakat Eropa Utara, Timur Tengah dan Afrika.
20
4. Usia
Reaksi dan ekspresi nyeri bervariasi pada tingkat usia yang berbeda,
misalnya pada bayi karena keterbatasan bahasa mereka berespon terhadap
nyeri dengan menangis, toddler dan prasekolah dengan karakteristik
perkembangan yang egosentrik akan berespon terhadap nyeri dengan
agresif dan tidak kooperatif (Wong, 2003).
5. Arti nyeri
Respon nyeri klien berbeda satu dengan yang lain tergantung pada
interpretasi masing-masing individu terhadap arti nyeri itu sendiri. Jika
klien beranggapan positif terhadap arti nyeri maka akan merespon nyeri
secara positif pula, demikian pula sebaliknya.
6. Lingkungan dan dukungan keluarga keluarga
Lingkungan yang asing dapat memperberat rasa nyeri dari klien,
sedangkan dukungan keluarga yang efektif dapat mengurangi respon
klien terhadap nyeri. Hal ini terjadi karena pengaktifan produksi
endorphin yang dapat mengeblok impuls nyeri sehingga intensitas nyeri
dapat meningkat atau menurun.
7. Jenis kelamin
Wanita lebih terbuka dalam merespon terhadap nyeri dibandingkan laki-
laki.
21
e. Pengkajian Nyeri pada Anak
Keluhan adalah cara paling akurat dalam memperoleh informasi tentang
lokasi dan intensitas nyeri pada anak. Masukan dari keluarga sangat penting
dan mungkin diperlukan jika anak tidak mau atau tidak dapat melaporkan
adanya nyeri bagi dirinya sendiri. Pengkajian nyeri mencakup beberapa hal
antara lain :
1. Faktor pencetus, yang memperberat dan memperingan nyeri, misalnya
nyeri yang timbul saat ditusuk jarum infus
2. Kualitas, deskripsi nyeri dan bagaimana nyeri dirasakan, misal nyeri
seperti tajam, menusuk, seperti digigit semut.
3. Daerah (lokasi), anak mungkin mampu menunjukkan lokasi terjadinya
nyeri, misalnya pada daerah yang dipasang infus.
4. Waktu, kapan timbul nyeri, tiba – tiba atau bertahap, berapa lama nyeri
dirasakan.
5. Intensitas
Pada anak usia prasekolah intensitas nyeri dapat dikaji melalui skala
peringkat nyeri wajah (rating faces scale) yang terdiri dari enam wajah
kartun yang direntang dari wajah tersenyum untuk tidak ada nyeri sampai
wajah menangis untuk nyeri paling buruk. Jelaskan pada anak bahwa
wajah menunjukkan seberapa besar nyeri yang dialami, bila tampak
22
bingung, tunjukkan wajah 1 untuk wajah yang tidak ada rasa nyeri pindah
dan tunjukkan ke wajah 5 untuk wajah yang sangat nyeri yang bisa
dibayangkan anak meskipun anak tidak menangis untuk merasa nyeri.
Jika anak masih bingung jelaskan gambar wajah satu persatu pada anak
menurut Hockenberry dan Wilson, (2007) adalah sebagai berikut:
1. Skala Analog Visual (Visual Analog Scale/VAS)
VAS adalah suatu garis lurus yang mewakili intensitas nyeri yang
terus-menerus dan pendeskripsi verbal pada setiap ujungnya. Skala
ini memberi klien kebebasan penuh untuk mengidentifikasi
keparahan nyeri.VAS dapat merupakan pengukuran keparahan nyeri
yang lebih sensitif karena klien dapat mengidentifikasi setiap titik
pada rangkaian dari pada dipaksa memilih satu kata atau satu angka
(Perry & Potter, 2005).
Visual Analog Scale (VAS) mengukur besarnya nyeri pada garis
sepanjang 10 cm. Biasanya berbentuk horizontal, tetapi mungkin saja
ditampilkannya secara vertikal. Garis ini digerakkan oleh gambaran
intensitas nyeri,misalnya : ”no hurt”, sampai” worst hurt”. Baik
skala vertikal maupun horizontal merupakan pengukuran yang sama
valid, tetapi VAS yang vertikal lebih sensitif menghasilkan score
yang lebih besar dan lebih mudah digunakan dari pada skala
horizontal. VAS ini dapat digunakan pada anak yang mampu
23
memahami perbedaan dan mengindikasikan derajat nyeri yang
sedang dialaminya (Hockenberry, 2007).
No Pain Worst pain ever
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No pain most pain
Gambar.1. Skala Analog Visual (Visual Analog Scale / VAS)
Sumber : www.health.vie.gov.au
2. Skala Intensitas Nyeri Numerik (Numeric Rating Scale/ NRS)
Skala penilaian numerik (NRS) lebih digunakan sebagai pengganti
alat pendeskripsi kata. Dalam hal ini, klien menilai nyeri dengan
menggunakan skala 0-5 atau 10 (banyaknya nomor bervarias).
Numeric Rating Scale (NRS) hampir sama dengan Visual Analog
Scale (VAS), tetapi memiliki angka-angka sepanjang garisnya.
Angka 0-10 atau 0-100 dan anak diminta untuk menunjukkan rasa
nyeri yang dirasakannya. Skala numerik ini dapat digunakan pada
anak yang lebih muda seperti 3-4 tahun atau lebih.
24
PAIN SCORE 0 – 10 NUMERICAL RANTING
0 – 10 Numerical Rating Scale
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Moderate worst Pain pain pain
Gambar .2. Skala Intensitas Nyeri Numeric (Numerical Rating Scale /
NRS)
Sumber : www.health.vie.gov.au
Dari skala di atas, tingkatan nyeri yang dapat diklasifikasikan sebagai
berikut :
Skala 1 : tidak ada nyeri
Skala 2-4 : nyeri ringan, dimana pasien belum mengeluh nyeri, atau
masih dapat ditolerir karena masih diambang rangsang.
Skala 5-6 : nyeri sedang, dimana pasien mulai merintih dan mengeluh
ada yang sambil menekan pada bagian yang nyeri.
Skala7-9 : termasuk nyeri hebat, pasien mungkin mengeluh sakit sekali
dan pasien tidak mampu melakukan kegiatan biasa.
25
Skala 10 : termasuk nyeri yang sangat, pada tingkat ini pasien tidak
dapat lagi mengenal dirinya.
2. Faces Rating Scale dari Wong Baker
Wong dan Baker (1988) mengembangkan skala wajah untuk
mengkaji nyeri pada anak-anak. Skala tersebut terdiri dari enam
wajah dengan profil kartun yang menggambarkan wajah dari wajah
yang sedang tersenyum (tidak merasakan nyeri) kemudian secara
bertahap meningkat menjadi wajah kurang bahagia, wajah yang
sangat sedih sampai wajah yang ketakutan (nyeri yang sangat). Anak-
anak pada usia 3 tahun dapat menggunakan skala wajah ini (Potter &
Perry, 2005).
Gambar .3.Faces Rating Scale dari Wong Baker
Sumber : www.partnersagainstpain.com
26
Jelaskan pada anak :
0 = Tidak nyeri : Tidak merasakan sakit
1 = Ringan : Untuk rasa yang sedikit sakit
2 = Sedang : Cukup sakit
3 = Agak berat : Lebih sakit lagi
4 = Lebih berat : Bila nyeri dirasa sakit sekali
5 = Panik : Bila nyeri dirasa sangat sakit sekali sehingga
tidak dapat dikendalikan
Hasil dari pengkajian nyeri dapat dijadikan pedoman untuk menentukan
strategi yang tepat untuk mengurangi nyeri yang ada.
f. Manajemen Nyeri
Untuk menurunkan respon nyeri akibat pemasangan infus dibutuhkan
manajemen nyeri yang mencakup pendekatan farmakologis dan non
farmakologis
1. Pendekatan farmakologis
Intervensi farmakologis dilakukan dalam kolaborasi dengan dokter,
namun perawat yang mempertahankan obat, mengkaji keefektifannya dan
melaporkan jika intervensi tersebut tidak efektif dan atau terjadi efek
samping. Intervensi ini meliputi pemberian analgesik dan agen anestesi.
27
2. Pendekatan non farmakologis
Pendekatan non farmakologis ini meliputi terapi es dan panas, distraksi,
teknik relaksasi dan imajinasi terbimbing.
Mengkombinasikan intervensi farmakologis dan non farmakologis adalah
cara yang efektif untuk menangani nyeri. Tindakan maksimal untuk
mengurangi nyeri dapat mencegah perasaan trauma pada anak dan
perawatan atraumatik sangat dibutuhkan dalam perawatan anak.
D. EMLA
1. Pengertian
Krim EMLA ( Eutectic Mixture of Local Anesthetics) adalah suatu krim
campuran eutektik dari 2 obat bius lokal lidokain 2,5% dengan prilokain 2,5%.
Ini merupakan suatu anestesi topikal yang dikembangkan untuk membius kulit
utuh, digunakan untuk meredakan dan mencegah rasa sakit yang terkait dengan
prosedur yang menyakitkan, seperti suntikan, pemasangan infus, pengambilan
darah ataupun pembedahan superficial.
2. Indikasi
Krim EMLA digunakan untuk anestesi topikal pada lapisan kulit pada
penggunaan penusukan jarum infus, pengambilan darah, ataupun prosedur
pembedahan superficial.
28
3. Cara kerja EMLA
Pemberian anestesi topikal (EMLA) pada pemasangan infus dapat mengeblok
impuls nyeri. Krim EMLA bekerja dengan menurunkan permeabilitas membran
sel terhadap ion natrium dan mengaktivasi saraf berserat besar delta A sehingga
akan mengeblok impuls dan potensial aksi tersebut tidak dapat dijalarkan ke
fase berikutnya yang berakibat persepsi nyeri tidak muncul di korteks serebri
(Olson, 2003).
Setelah obat berefek, kemudian obat akan diserap ke dalam pembuluh darah
dan dieliminasi. Proses metabolisme dan eksresi obat golongan amida ini akan
dihidrolisis oleh enzim mikrosom hati dan akan diubah menjadi yang lebih larut
air kemudian akan dikeluarkan melalui urin.
4. Tehnik pemberian EMLA
Untuk mengurangi trauma pada anak terhadap rasa nyeri prosedural akibat
pemasangan infus dapat digunakan teknik dibawah ini : (Wong, 2003)
a. Berikan EMLA secara topikal di atas area yang akan dipasang infus tutup
dengan balutan berperekat, tunggu selama 60 menit
b. Biarkan persiapan kulit tersebut mengering dengan sempurna sebelum kulit
ditusuk.
c. Gunakan jarum tajam dan baru dengan ukuran kecil sesuai dengan anak
29
d. Kurangi persepsi nyeri dengan cara distraksi dengan percakapan, buat anak
berkonsentrasi (misalnya dengan mendengarkan cerita), tempatkan kompres
dingin di area pemasangan infus selama satu menit sebelum tindakan serta
katakan pada anak untuk memberitahu perawat ketika merasakan sesuatu.
e. Dorong keberadaan orang tua bila mereka ingin berpartisipasi
f. Restrain anak hanya bila diperlukan agar prosedur dapat dilakukan dengan
aman.
g. Anjurkan orang tua untuk menyamankan anak setelah prosedur dan berikan
pujian pada anak yang lebih besar.
Dari beberapa point di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu teknik yang
digunakan untuk mengurangi stres pada anak saat pemasangan infus adalah
dengan pemberian EMLA dan distraksi.
5. Pedoman Penggunaan EMLA
Prosedur penggunaan EMLA dapat dijabarkan sebagai berikut: (Wong, 2003).
Hal tersebut di atas merupakan pedoman yang luas untuk menghindari
toksisitas sistemik dalam pemberian EMLA pada kulit pasien yang utuh dan
normal dengan fungsi ginjal serta fungsi hati yang normal (Wong, 2003).
a. Jelaskan pada anak bahwa EMLA seperti krim ajaib yang dapat
menghilangkan rasa sakit.
30
b. Berikan lapisan tebal EMLA di atas kulit utuh normal untuk menganestesi
area tersebut (kira – kira sepertiga dari kemasan 5 gram dapat digunakan
untuk pungsi bersifat lokal dan superfisial, seperti injeksi intradermal atau
pungsi jari).
c. Tempatkan balutan berperekat yang transparan di atas EMLA dan pastikan
bahwa krim tetap berlapis tebal.
d. Beri label pada balutan tentang tanggal dan waktu pemakaian EMLA
untuk membedakannya dari balutan lain. Instruksikan anak yang lebih besar
untuk tidak memegang balutan tersebut. Awasi anak kecil atau berkompromi
secara kognitif dengan anak selama pemasangan.
e. Biarkan EMLA pada kulit selama 60 menit untuk pungsi superfisial dan 120
menit untuk penetrasi dalam. Krim EMLA dapat dipakai di rumah dan
mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk pasien berkulit gelap
dan atau lebih tebal. Anestesi dapat berakhir sampai tiga jam setelah EMLA
dihilangkan.
f. Lepaskan balutan sebelum prosedur dan usap krim dari kulit. Dengan
perekat transparan, pegang sisi yang berlawanan, sementara memegang
balutan paralel terhadap kulit, tarik sisi tersebut saling menjauh satu sama
lain untuk meregangkan atau mengendorkan balutan.
31
g. Observasi warna kulit, baik kemerahan atau kepucatan. Bila tidak ada reaksi
kulit yang nyata, EMLA mungkin tidak terpenetrasi dengan adekuat. Uji
sensitivitas kulit dan bila perlu ulangi.
h. Gores sedikit kulit anak untuk menunjukkan bahwa “kulit sudah tidur”
sehingga kulit tidak dapat merasakan tertusuk jarum sekalipun.
i. Setelah prosedur, kaji respon prilaku, jika anak marah gunakan skala nyeri
FACES untuk membantu anak membedakan antara nyeri dan takut.
6. Kontraindikasi
EMLA tidak boleh diberikan kepada : bayi dengan usia di bawah satu bulan,
pasien methemoglobin kongenital/idiopatik, bayi di bawah 12 bulan yang
menerima pengobatan agen methemoglobin (sulfonamid, fenitoin, fenobarbital,
asetaminofen). Methemoglobin merupakan bentuk disfungsional dari
hemoglobin yang dapat mengurangi kapasitas pengangkutan oksigen darah dan
menyebabkan sianosis serta hipoksemia. Penggunaan metilen biru intravena
dengan segera dapat menghilangkan methemoglobinemia. Krim EMLA juga
dikontraindikasikan pada individu dengan riwayat sensitivitas yang diketahui
atau alergi terhadap anestesi lokal jenis amida (lidokain, prilokain, mepivikain,
buvikain, etidokain) atau terhadap komponen lain dari produk.
32
7. Dosis pemakaian
Area pemberian maksimum krim EMLA yang dianjurkan pada kulit utuh
untuk bayi dan anak-anak adalah jika berat badan anak sampai 10 kg diberikan
100 cm2, 10 – 20 kg diberikan 600 cm2, diatas 20 kg diberikan 2000 cm2.
33
BAB III
KERANGKA KONSEP, HIPOTESIS, DAN
DEFINISI OPERASIONAL
Pada bab ini akan diuraikan tentang kerangka konsep penelitian, hipotesis dan
definisi operasional. Kerangka konsep merupakan justifikasi ilmiah terhadap
penelitian yang dilakukan dan memberi landasan terhadap topik yang dipilih
dalam penelitian (Hidayat, 2007). Hipotesis adalah sebuah pernyataan sederhana
mengenai perkiraan hubungan antara variabel-variabel yang sedang diteliti,
sedangkan definisi operasional memberikan deskripsi lengkap mengenai metode
dengan konsep yang akan diteliti (Dempsey & Dempsey, 2002).
A. Kerangka Konsep
Kerangka konsep pada penelitian ini menggambarkan ada tidaknya pengaruh
pemberian EMLA terhadap tingkat nyeri anak usia prasekolah yang dilakukan
tindakan pemasangan infus. Adapun kerangka konsep penelitian ini
digambarkan dalam bentuk bagan yang terdiri dari variabel independent dan
variabel dependent, sebagai berikut :
34
Skema 3.1 Kerangka Konsep
Penelitian
Kerangka konsep ini akan menjelaskan tentang variabel-variabel yang dapat
diukur dalam penelitian ini. Kerangka konsep pada penelitian ini meliputi 3
komponen, yaitu : variabel independent (variabel bebas), variabel dependent
(variabel terikat) , dan variabel confounding (variabel perancu).
Variabel Dependen
EMLA Tingkat Nyeri
Variabel Confounding: 1. Jenis Kelamin 2. Kehadiran orang tua / keluarga 3. Ketakutan 4. Pengalaman Infus sebelumnya
Variabel Independen
35
Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut :
1. Variabel dependent (variabel terikat)
Variabel dependent adalah variabel yang berubah akibat perubahan
variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat nyeri.
2. Variabel independent (variabel bebas)
Variabel independent adalah variabel yang bila berubah akan
mengakibatkan perubahan variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian
ini adalah pemberian krim EMLA pada anak usia prasekolah yang
dilakukan pemasangan infus.
3. Variabel confounding (variabel perancu)
Variabel confounding adalah jenis variabel yang berhubungan dengan
variabel dependent dan variabel independent, tetapi bukan merupakan
variabel antara (Sastroasmoro & Ismail, 2002). Variabel confounding
dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, kehadiran keluarga, ketakutan,
dan pengalaman infus sebelumnya.
B. Hipotesis Penelitian
Menurut La Biondo-Wood dan Haber, 1994 (dalam Nursalam, 2008),
hipotesis adalah suatu pernyataan asumsi tentang hubungan antara dua atau
lebih variabel yang diharapkan bisa menjawab suatu pernyataan dalam
penelitian. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu ada
pengaruh pemberian EMLA terhadap tingkat nyeri anak usia prasekolah
yang dilakukan pemasangan infus.
37
C. Definisi Operasional
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel, definisi operasional, cara ukur, hasil ukur dan skala ukur
Variabel Definisi Operasional Alat dan Cara Ukur Hasil Ukur Skala
Variabel Bebas
EMLA
Tindakan memberikan krim
EMLA pada anak usia
prasekolah 60 menit sebelum
dilakukan pemasangan infus
- Krim EMLA
- Observasi ( check list )
0 = perawat memberikan krim
EMLA
1 = perawat tidak memberikan
krim EMLA
Nominal
Variabel Terikat
Tingkat nyeri
Rasa sakit yang dirasakan anak
usia prasekolah akibat
pemasangan infus saat tindakan
penusukan langsung
Anak menunjuk pada
gambar Wong Baker Faces
Scale
0 = nyeri tidak dirasakan oleh
anak
1 = nyeri dirasakan sedikit saja
2 = nyeri agak dirasakan oleh
anak
3 = nyeri yang dirasakan anak
lebih banyak
4 = nyeri yang dirasakan anak
Interval
38
secara keseluruhan
5 = nyeri sekali dan anak
menjadi menangis
0 = nyeri ringan ( 0 – 3 )
1 = nyeri berat ( 4 – 5 )
Ordinal
Variabel Perancu:
1.Jenis kelamin
2.Kehadiran
orang tua /
keluarga
3.Ketakutan anak
Jenis seks:laki-laki atau
perempuan
Keterlibatan orang tua /
keluarga yang terdekat di tempat
tindakan pemasangan infus
dilakukan
Perasaan yang dirasakan anak
terhadap tindakan pemasangan
infus yang dilakukan
Observasi ( check list )
Observasi ( check list )
Observasi
0 = laki-laki
1 = perempuan
0 = hadir
1 = tidak hadir
0 = tidak takut
1 = takut
Nominal
Nominal
Nominal
39
4. Pengalaman
Sebelumnya
Pengalaman dilakukan tindakan
pemasangan infus sebelumnya
Kuesioner
0 = ada
1 = tidak ada
Nominal
39
BAB IV
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Desain penelitian merupakan keseluruhan rencana peneliti untuk mendapatkan
jawaban dari pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis penelitian (Polit &
Hungler, 1999). Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuasi
eksperimental yang bertujuan menguji hubungan sebab akibat (Burns & Grove,
2003). Desain kuasi eksperimental adalah metode penelitian eksperimen dengan
menggunakan kelompok kontrol, tetapi tidak sepenuhnya untuk mengontrol
variabel-variabel luar yang mempengaruhi penelitian (Sugiyono, 2008). Jenis
kuasi eksperimental pada penelitian ini adalah Nonequivalent control group,
after only design, karena pemilihan kelompok intervensi dan kelompok kontrol
tidak diacak. After only design karena penelitian ini tidak melakukan
pengukuran sebelum intervensi, pengukuran hanya dilakukan setelah selesai
intervensi. Penelitian ini melibatkan 2 kelompok yaitu; Kelompok anak usia
prasekolah yang dilakukan pemasangan infus dengan diberikan krim EMLA
sebagai kelompok intervensi dan kelompok anak usia prasekolah yang
dilakukan pemasangan infus dengan tidak diberikan krim EMLA sebagai
kelompok kontrol.
40
B. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi dalam penelitian adalah obyek atau subyek yang mempunyai
kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian disimpulkannya ( Sugiyono, 2004 dalam Hidayat,
2008 ). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anak usia prasekolah
yang dirawat di Ruang Anak Gedung A RSCM Jakarta.
2. Sampel
Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah
dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Hidayat, 2008). Pemilihan
sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara purposif sampling. Pada
cara ini peneliti memilih responden berdasarkan kepada pertimbangan
subyektifnya, bahwa responden tersebut dapat memberikan informasi yang
memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sastroasmoro & Ismael,
2002). Pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan
menentukan kriteria sampel, yang meliputi kriteria inklusi dan kriteria
eksklusi, dimana kriteria tersebut menentukan dapat dan tidaknya sampel
tersebut digunakan.
Kriteria inklusi merupakan kriteria dimana subjuk penelitian mewakili
sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel, sedangkan
kriteria eksklusi merupakan kriteria dimana penelitian tidak dapat mewakili
sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian
(Nursalam, 2003).
41
Kriteria inklusi pada sampel penelitian ini adalah :
a. Anak usia prasekolah (3-6 tahun)
b. Akan dilakukan pemasangan infus
c. Anak mampu berkomunikasi secara verbal dan non verbal
d. Ibu/keluarga bersedia apabila anak menjadi responden penelitian
e. Ibu/keluarga mampu membaca, menulis, dan berkomunikasi secara
verbal dan non verbal
Kriteria eksklusi pada sampel penelitian ini adalah :
a. Kondisi anak sangat lemah dan mengalami gangguan kesadaran
b. Ibu/keluarga tidak kooperatif
Perkiraan besar sampel dapat ditentukan dengan mengetahui rerata, standar
deviasi pada penelitian sebelumnya. Rumus perhitungan sampel pada
penelitian menggunakan uji hipotesis rata-rata pada 2 kelompok
independent menurut Ariawan ( 1998 ) adalah sebagai berikut :
n = 2o2 ( Z1-Ó/2 + Z1-β)2
( µ1 - µ2 )2
Keterangan :
N = Besar sampel minimum
Z1-Ó/2 = Derajat kemaknaan
Z1-β = Kekuatan uji
µ1 = Rata-rata skala nyeri pada kelompok intervensi
µ2 = Rata-rata skala nyeri pada kelompok kontrol
Ó = Standar deviasi dari beda dua rata-rata berpasangan penelitian awal
42
Peneliti membuat perhitungan besar sampel minimal berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan sebelumnya. Sulistiyani (2009), yang meneliti
mengenai pengaruh kompres es batu terhadap nyeri akibat tindakan
pemasangan infus pada anak usia prasekolah. Diperoleh rata-rata skala
nyeri pada kelompok kontrol adalah 3, 1 dengan standar deviasi 1, 148,
sedangkan rata-rata skala nyeri kelompok intervensi adalah 3, 28 dengan
standar deviasi 1, 420.
{ ( n1 – 1 ) S12 + ( n2 – 1 ) S2
2 )}
Sp2 =
( n1 – 1 ) + ( n2 - 1 )
{ ( 32 – 1 ) 1,4202 + ( 32 – 1 ) 1,1482 )} Sp 2 =
( 32 – 1 ) + ( 32 – 1 ) 62,62 + 40,92
Sp 2 = 62 = 1,67
Keterangan :
S1 2 = Standar deviasi pada kelompok intervensi
S2 2 = Standar deviasi pada kelompok kontrol
Maka besar sampel yang diperlukan adalah :
n = 2o2 ( Z1-Ó/2 + Z1-β)2
( µ1 - µ2 )2
n = 2 x 1,67 ( 1,96 + 0,84 )2
( 3,28 – 3,31 )2
n = 30
43
Untuk mencegah kejadian drop out atau kesalahan teknis maka besar sampel
ditambah 10 %.Berdasarkan hal tersebut maka jumlah sampel yang
dibutuhkan untuk penelitian ini adalah : untuk kelompok intervensi sebesar
20 orang dan kelompok kontrol 20 orang. Total sampel adalah 40 orang.
Besarnya sampel pada saat penelitian sesuai dengan perencanaan yang telah
dibuat sebelumnya yaitu 40 orang yang terdiri atas 20 orang untuk kelompok
intervensi dan 20 orang untuk kelompok kontrol. Hal tersebut dikarenakan
tidak adanya responden yang drop out.
C. Tempat penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di Ruang Anak Gedung A RSCM Jakarta
untuk kelompok intervensi dan kelompok kontrol, dimana ruangan tersebut
sudah menerapkan krim EMLA untuk meminimalkan nyeri pada anak yang
dilakukan pemasangan infus.
D. Waktu Penelitian
Pelaksanaan penelitian dengan judul “Pengaruh pemberian EMLA terhadap
tingkat nyeri anak usia prasekolah yang dilakukan pemasangan infus di Ruang
Anak Gedung A RSCM Jakarta” akan dilakukan di Ruang Anak Gedung A
RSCM Jakarta pada bulan Februari 2013.
.
44
E. Etika penelitian
Etika penelitian adalah suatu sistem nilai yang normal, yang harus dipatuhi
oleh peneliti saat melakukan aktifitas penelitian yang melibatkan responden,
meliputi kebebasan dari adanya ancaman, kebebasan dari eksploitasi,
keuntungan dari penelitian tersebut, dan resiko yang didapatkan
(Nursalam,2003). Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mendapat
rekomendasi dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan permintaan ke direktur
RSCM Jakarta. Setelah mendapat persetujuan, barulah melakukan penelitian
memenuhi beberapa prinsip etik sebagai berikut :
1. Right to self-determination
Responden atau orang tua mempunyai hak otonomi untuk berpartisipasi
atau tidak berpartisipasi dalam penelitian.Sebelum melakukan penelitian,
peneliti memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada responden dan
keluarganya kemudian menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian
yang akan dilakukan. Peneliti juga akan menjelaskan tentang
teknik/prosedur pelaksanaan penelitian, manfaat dan resikonya bahwa apa
yang akan dilakukan tidak akan membahayakan anak. Setelah
mendapatkan penjelasan dari peneliti, responden atau orang tua diberi
kesempatan untuk memberikan persetujuan atau menolak berpartisipasi
dalam penelitian. Setelah keluarga menyetujui penelitian yang akan
dilakukan, kemudian keluarga menandatangani lembar persetujuan yang
telah disiapkan oleh peneliti. Karena responden dalam penelitian ini
45
adalah anak usia prasekolah (3-6 tahun), maka yang memberi persetujuan
adalah orang tuanya.
2. Right to privacy and dignity
Dalam penelitian ini peneliti menjaga privasi dan martabat responden.
Peneliti menjaga semua informasi yang diperoleh dari responden dan
hanya memakainya untuk keperluan penelitian. Data-data yang telah
dikumpulkan peneliti, disimpan dengan baik dan jika sudah tidak
diperlukan lagi data tersebut akan dimusnahkan.
3. Right to anonymity and confidentiality
Untuk menjaga kerahasiaan responden, peneliti tidak mencantumkan
nama responden pada lembar pengumpulan data, cukup memberi inisial
nama pada masing-masing lembar tersebut. Untuk menjaga kerahasiaan
tersebut, peneliti hanya menggunakan kelompok data tersebut saja yang
disajikan atau dilaporkan sebagai hasil penelitian. Data yang telah
dikumpulkan, peneliti simpan dengan baik dan jika sudah tidak
diperlukan lagi data responden akan dimusnahkan.
4. Right to protection from discomfort and harm
Kenyamanan responden dan resiko dari perlakuan yang diberikan selama
penelitian tetap dipertimbangkan dalam penelitian ini. Untuk memberikan
kenyamanan pada responden selama prosedur pemasangan infus, peneliti
akan memberikan krim EMLA sebelum tindakan pemasangan infus.
46
F. Alat Penelitian
1. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa
kuesioner dan lembar observasi.
a. Berdasarkan rekomendasi dari Wong dan penelitian yang dilakukan tahun
2002 di Amerika tentang keefektifan krim EMLA dalam menurunkan
intensitas nyeri, maka pada penelitian ini digunakan instrumen krim
EMLA.
b. Dalam pengumpulan data dengan menggunakan lembar observasi tentang
respon nyeri dan intensitas nyeri selama pemasangan infus. Untuk
intensitas nyeri diukur dengan menggunakan faces scale dari Wong-
Baker (Wong, 2003), dimana observasi dilakukan oleh peneliti.
c. Kuesioner berisi tentang karakteristik responden, yang meliputi: tanggal
lahir/umur, jenis kelamin, keluarga yang mendampingi anak saat prosedur
dilakukan, ketakutan anak. Pendamping responden diminta mengisikan
jawaban di tempat yang disediakan pada kuesioner.
2. Uji Validitas dan Reliabilitas
Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini (Baker Faces Pain Scale) sudah
baku, sehingga tidak diujicobakan validitasnya. Uji intereter reliability tidak
dilakukan karena penilaian nyeri diinformasikan langsung oleh responden
dengan cara menunjuk pada gambar wajah yang sudah disiapkan (Wong
Baker Faces Pain Scale) sementara pelaksanaan prosedur pemasangan infus
dilakukan oleh peneliti dan asisten peneliti.
47
G. Prosedur Pengumpulan Data
1. Prosedur administrasi
a. Peneliti mengajukan kaji etik penelitian pada komite etik PSIK FKK
UMJ setelah ujian proposal
b. Peneliti mengajukan surat permohonan ijin penelitian kepada Ketua
Program PSIK FKK UMJ yang ditujukan kepada Direktur RSCM
Jakarta,melalui Kepala Diklat RSCM Jakarta.
c. Mengurus surat ijin penelitian ke RSCM Jakarta untuk ijin
penelitian, kemudian peneliti menyampaikan ijin penelitian kepada
Supervisor Ruang Anak Gedung A RSCM Jakarta.
d. Setelah mendapatkan ijin penelitian, peneliti menyampaikannya
kepada beberapa pihak terkait di antaranya Head Nurse dan staf
Ruang Anak Gedung A RSCM Jakarta.
2. Prosedur Teknis
a. Peneliti melakukan penelitian di Ruang Anak Gedung A RSCM
Jakarta, baik untuk kelompok intervensi dan kelompok kontrol.
b. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian yang akan
dilakukan serta bagaimana proses pelaksanaannya kepada kepala
ruangan terkait.
c. Peneliti juga meminta kepada kepala ruangan untuk bisa menunjuk 6
orang perawat (2 orang untuk tiap shifnya) sebagai asisten peneliti
guna membantu proses penelitian dan menghindari bias.
48
d. Peneliti bersama kepala ruangan menentukan perawat di ruang anak
sebagai asisten peneliti yang berjumlah 6 orang, 2 orang untuk tiap
shifnya dengan kriteria : tingkat pendidikan minimal Diploma III
Keperawatan, terlatih melakukan pemasangan infus.
e. Setelah asisten peneliti ditentukan, peneliti melakukan sosialisasi
terkait penelitian yang akan dilakukan menjelaskan maksud dan
tujuan, bagaimana proses pelaksanaan penelitian tersebut serta
menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kuesionar dan
penggunaan Wong Baker Pain Scale.
f. Sebelumnya peneliti memberikan contoh terlebih dahulu kepada
asisten peneliti guna mempersamakan persepsi,langkah-langkah yang
dilakukan peneliti dalam memberikan contoh, seperti berikut ini :
1. Peneliti/asisten peneliti berkolaborasi dengan dokter untuk
pemberian EMLA pada pasien yang akan dilakukan pemasangan
infus.
2. Peneliti/asisten peneliti mencari dan memilih calon responden
sesuai kriteria inklusi dan eksklusi.
3. Menemui calon responden meminta persetujuan dari keluarga
untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Sebelum melakukan
penelitian, peneliti memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada
responden dan keluarganya. Kemudian menjelaskan maksud dan
tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.
49
4. Peneliti kemudian memberikan penjelasan tentang
tehnik/prosedur pelaksanaan penelitian, manfaat dan resikonya
bahwa apa yang akan dilakukan tidak akan membahayakan
5. Setelah keluarga menyetujui penelitian yang akan dilakukan
kemudian keluarga menandatangani lembar persetujuan yang
telah disiapkan oleh peneliti. Karena responden dalam penelitian
ini adalah anak usia prasekolah (3-6 tahun), maka yang memberi
persetujuan adalah orang tua.
6. Setelah kuesioner diisi oleh keluarga responden, peneliti bersama
dengan perawat ruangan mempersiapkan prosedur pemasangan
infus pada responden.
7. Peneliti menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan pada
responden dan orang tua. Sebelum melakukan tindakan
peneliti/asisten peneliti menanyakan kepada orang tua responden
apakah orang tua ingin mendampingi anaknya saat dilakukan
pemasangan infus di ruang tindakan.
8. Setelah mengoleskan krim EMLA pada tempat pemasangan
infus dan ditunggu selama 60 menit kemudian mengobservasi
respon nyeri responden pada saat dilakukan pemasangan infus.
Sebelum tindakan tersebut dilakukan, peneliti atau asisten
9. peneliti terlebih dahulu menulis karakteristik demografi
responden.
50
10. Kemudian peneliti meminta responden untuk menginformasikan
rasa nyerinya dengan menunjuk gambar yang sudah disiapkan
oleh peneliti.
11. Peneliti memberikan reinforcement positif pada responden dan
keluarga atas keterlibatannya dalam penelitian, serta kepada
asisten peneliti.
g. Setelah memberikan contoh kemudian peneliti melanjutkan langlah-
langkah prosedur tehnik penelitian seperti yang telah dicontohkan.
h. Asisten peneliti 2 melakukan persiapan dengan mencari area
pemasangan infus dan melaksanakan infus. Peneliti/asisten peneliti
memberikan krim EMLA pada responden (kelompok intervensi) 60
menit sebelum pemasangan infus sampai 5 menit setelah selesai
pemasangan infus.
i. Responden diminta untuk menginformasikan langsung tingkat nyeri
yang dilakukan dengan cara menunjuk pada gambar wajah yang
sudah disiapkan (Wong Baker Pain Scale) saat pemasangan infus
dilakukan, bagi responden yang tidak mau menunjuk pada gambar
yang sudah disiapkan, asisten 2 memotret ekspresi wajah responden
saat dilakukan prosedur.Setelah responden tenang kembali, asisten
peneliti memperlihatkan foto tersebut kepada responden dan
responden diminta untuk mencocokkannya dengan gambar skala
wajah yang sudah disiapkan.
j. Asisten peneliti memberikan pujian pada seluruh responden dan
keluarga atas keterlibatannya dalam penelitian.
51
k. Tahap selanjutnya peneliti melakukan proses editing
l. Untuk menghindari terjadinya bias pada hasil penelitian ini, maka
prosedur penelitian umumnya dilakukan oleh asisten peneliti.Namun
demikian peneliti selalu mengevaluasi proses yang sudah dilakukan
oleh asisten peneliti.
H. Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai
dilakukan. Tahapan pengolahan data penelitian terbagi atas 4 tahap (Hastono,
2007). Tahapan pengolahan data yang dilalui adalah :
1. Editing
Peneliti melakukan pemeriksaan atau editing data yang diperoleh dengan
melakukan pengecekan terhadap isian lembar observasi apakah
pertanyaan-pertanyaan telah terisi semua. Proses ini dilakukan untuk
memastikan bahwa data yang diperoleh sudah lengkap, jelas, relevan
dan konsisten.
2. Coding
Coding merupakan pemberian kode pada setiap variabel untuk
mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data dan mempercepat
pada saat entry data. Pada tahap ini peneliti melakukan pengkodean
terhadap variabel.
52
3. Entry Data
Peneliti memproses data dengan cara melakukan entry data dari masing-
masing responden ke dalam program komputer.Pada tahapan ini yang
dilakukan peneliti adalah memasukan data dengan lengkap dan sesuai
dengan koding dan tabulating ke dalam paket program komputer dengan
tujuan untuk melakukan analisis sesuai dengan tujuan penelitian.
4. Cleaning
Setelah data dimasukan ke dalam komputer, peneliti melakukan
pengecekan kembali untuk memastikan apakah data yang sudah di entry
ada kesalahan atau tidak dan pengecekan terhadap kemungkinan data
yang hilang dengan cara melakukan list dari variabel yang ada serta
pengecekan kemungkinan adanya kesalahan pengkodingan. Setelah
dipastikan tidak terdapat kesalahan dalam entry data maka peneliti
melakukan analisis dengan menggunakan program komputer.
I. Analisa Data
1. Analisis Univariat
Analisis digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan
karakteristik masing-masing variabel yang diteliti, yaitu jenis kelamin,
kehadiran keluarga selama prosedur pemasangan infus, ketakutan
responden, pengalaman responden dalam prosedur pemasangan infus
sebelumnya, tindakan pemberian krim EMLA, serta tingkat nyeri
responden. Pada analisis univariat, hasil analisis data disajikan dalam
distribusi frekuensi dan prosentase atau proporsi.
53
2. Analisa Bivariat
Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara kedua
variabel. Pada penelitian ini uji bivariat untuk mengetahui perbedaan
tingkat nyeri pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Uji yang
dipergunakan adalah uji beda 2 mean independent (independent sample
test), yaitu uji statistik untuk mengetahui beda mean pada dua kelompok
data independen (Hastono, 2007).
Tabel 4.1. Uji Statistik
Variabel Independen Variabel Dependen Uji Statistik
EMLA Tingkat nyeri Independen t-test
54
BAB V
HASIL PENELITIAN
Bab ini menguraikan secara lengkap hasil penelitian pengaruh pemberian EMLA
terhadap tingkat nyeri anak usia prasekolah yang dilakukan pemasangan infus di
Ruang Anak Gedung A RSCM Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 minggu,
yaitu dari tanggal 4 Februari sampai 16 Februari 2013. Jumlah responden pada
penelitian ini sebanyak 40 responden anak usia prasekolah yang dilakukan
pemasangan infus terbagi dalam dua kelompok, yaitu 20 responden kelompok
intervensi dan 20 responden kelompok kontrol. Data yang didapat dianalisis dengan
menggunakan analisis univariat dan bivariat sebagai berikut :
A. Analisis Univariat
Dalam analisa univariat ini akan menjelaskan secara deskriptif mengenai
variabel-variabel penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, kehadiran
keluarga/orang tua selama prosedur pemasangan infus, ketakutan responden,
pengalaman responden dalam prosedur pemasangan infus sebelumnya, tindakan
pemberian EMLA, serta tingkat nyeri responden.
1. Gambaran karakteristik responden
Gambaran karakteristik anak usia prasekolah yang dilakukan pemasangan
infus di Ruang Anak Gedung A RSCM Jakarta dapat dilihat pada tabel 5.1 di
bawah ini :
55
Tabel 5.1
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Kehadiran Keluarga, Ketakutan anak, dan Pengalaman di Infus Sebelumnya, Februari 2013.
No Variabel Kelompok Intervensi (n = 20)
Kelompok Kontrol (n = 20)
1. Jenis Kelamin a. Laki-laki b. Perempuan
12 60,0 8 40,0
9 45,0 11 55,0
2. Kehadiran Keluarga a. Hadir b. Tidak Hadir
16 80,0 4 20,0
18 90.0 2 10,0
3. Ketakutan Anak a. Takut b. Tidak Takut
9 45,0 11 55,0
14 70,0 6 30,0
4. Pengalaman di Infus a. Ada b. Tidak Ada
19 95,0 1 5,0
15 75,0 5 25,0
Tabel 5.1, menunjukkan lebih banyak responden pada kelompok intervensi
berjenis kelamin laki-laki yaitu 60 %, sedangkan pada kelompok kontrol 55 %
responden berjenis kelamin perempuan.Sementara itu distribusi kehadiran
keluarga sama untuk masing-masing kelompok baik kelompok intervensi
maupun kelompok kontrol. Sebagian besar keluarga hadir saat anaknya
dilakukan pemasangan infus yaitu 80 % pada kelompok intervensi dan 90 %
pada kelompok kontrol. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pada
kedua kelompok responden terdapat kehadiran keluarga saat prosedur
pemasangan infus dilaksanakan.
Berdasarkan ketakutan anak seperti pada tabel 5.1, menunjukkan pada kelompok
intervensi 55 % anak tidak mengalami ketakutan saat dilakukan prosedur
56
pemasangan infus dilaksanakan.Sedangkan pada kelompok kontrol 70 % anak
mengalami ketakutan saat dilakukan prosedur pemasangan infus dilakukan.
Demikian secara keseluruhan baik responden pada kelompok intervensi maupun
kelompok kontrol ketakutan saat dilakukan prosedur pemasangan infus.
Berdasarkan pengalaman anak akan prosedur pemasangan infus sebelumnya
seperti tersaji pada tabel 5.1, menunjukkan pada kelompok intervensi 95 % anak
sudah pernah mengalami prosedur pemasangan infus sebelumnya, sedangkan
pada kelompok kontrol 75 % anak sudah pernah mengalami prosedur
pemasangan infus sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar
responden pada kedua kelompok sudah pernah mengalami prosedur pemasangan
infus sebelumnya.
2. Tingkat nyeri
Perbedaan tingkat nyeri responden dinilai dengan menggunakan Wong
Baker Faces ditunjukkan pada tabel 5.2
57
Tabel 5.2
Distribusi Tingkat Nyeri Dirasakan Responden Saat dilakukan Pemasangan Infus
di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Februari 2013
No Tingkat Nyeri
Kelompok
Intervensi
(n=20)
Kelompok
Kontrol
(n=20)
n % n %
1. Nyeri tidak dirasakan oleh anak 7 35,0 0 0
2. Nyeri dirasakan sedikit saja 6 30,0 0 0
3. Nyeri agak dirasakan oleh anak 5 25,0 0 0
4. Nyeri yang dirasakan anak lebih banyak 0 0 1 2,5
5. Nyeri yang dirasakan anak secara
keseluruhan
2 10,0 7 35,0
6. Nyeri sekali dan anak menjadi menangis 0 0 12 60,0
Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa proporsi pada kelompok intervensi
yang mengalami nyeri tertinggi 35 % ( n= 7), yaitu pada tingkat nyeri tidak
dirasakan oleh anak. Proporsi pada kelompok kontrol yang tertinggi 60 % ( n=
12 ) yaitu pada tingkat nyeri sekali dan anak menjadi menangis.Tingkat nyeri
dalam Wong Baker Faces Pain Scale adalah nyeri tidak dirasakan oleh anak,
nyeri dirasakan sedikit saja, nyeri agak dirasakan oleh anak, nyeri yang dirasakan
anak lebih banyak, nyeri yang dirasakan anak secara keseluruhan, nyeri sekali
dan anak menjadi menangis.
58
B. Analisis Bivariat
Pada Analisis bivariat ini peneliti akan melakukan uji hipotesis penelitian,
menguraikan ada tidaknya pengaruh pemberian EMLA terhadap tingkat nyeri
anak usia prasekolah yang dilakukan pemasangan infus di Ruang Anak Gedung
A RSCM Jakarta pada kelompok intervensi (yang diberikan EMLA) dan pada
kelompok kontrol (tidak diberikan EMLA), serta apakah ada perbedaan yang
bermakna antara kedua kelompok tersebut.
1. Perbedaan rata-rata skor nyeri anak usia prasekolah yang dilakukan
pemasangan infus terhadap pemberian EMLA pada kelompok
intervensi dan kelompok kontrol.
Tabel 5.3
Rata-rata Skor Nyeri Anak Usia Prasekolah
yang dilakukan Pemasangan Infus Terhadap Pemberian EMLA
di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Februari 2013
Kelompok Mean SD SE P value N
Intervensi 1,20 1,240 0,277 0,00
20
Kontrol 4,55 0,605 0,135 20
Tabel 5.3, menunjukkan bahwa rata-rata tingkat nyeri anak usia prasekolah yang
diberikan EMLA saat dilakukan pemasangan infus adalah 1,20, sedangkan
tingkat nyeri anak usia prasekolah yang tidak diberikan EMLA saat dilakukan
pemasangan infus adalah 4,55. Hasil uji statistik didapatkan p value 0,00 dengan
ὰ < 0,05, sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan rata-rata
59
tingkat nyeri antara anak usia prasekolah yang diberikan EMLA saat dilakukan
pemasangan infus dengan anak usia prasekolah yang tidak diberikan EMLA saat
dilakukan pemasangan infus.
2. Pengaruh pemberian EMLA terhadap tingkat nyeri anak usia
prasekolah yang dilakukan pemasangan infus.
Tabel 5.4
Distribusi Responden Menurut Tingkat nyeri
Anak Usia Prasekolah yang Dilakukan Pemasangan Infus
Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Februari 2013
Kelompok
Tingkat Nyeri Jumlah OR
(95%Cl)
P
Value Nyeri Ringan Nyeri Berat
n % N % n %
Intervensi 18 90,0 2 10,0 20 100 18,00 0,00
Kontrol 1 5,0 19 95,0 20 100 (14,24-2053)
Jumlah 19 47,5 21 52,5 40 100
Hasil analisis menunjukkan bahwa 90 % anak usia prasekolah yang diberikan
EMLA saat dilakukan pemasangan infus mengalami nyeri ringan. Sedangkan
anak usia prasekolah yang tidak diberikan EMLA saat dilakukan pemasangan
infus sebanyak 5 % anak mengalami nyeri ringan. Hasil uji statistik diperoleh p
value 0,00, maka dapat disimpulkan ada perbedaan tingkat nyeri yang signifikan
antara anak usia prasekolah yang berikan EMLA saat dilakukan pemasangan
infus dengan anak usia prasekolah yang tidak diberikan EMLA saat dilakukan
pemasangan infus. Dari hasil analisis diperoleh pula nilai OR =18,00, artinya
60
anak usia prasekolah yang diberi EMLA saat dilakukan pemasangan infus
mempunyai peluang 18 kali untuk mengalami nyeri ringan dibandingkan anak
yang tidak diberi EMLA.
61
BAB VI
PEMBAHASAN
Bab ini akan menjelaskan keterbatasan penelitian yang telah dilaksanakan dan
membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bab terdahulu
dengan berlandaskan pada teori dan penelitian-penelitian terkait.
A. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan yang peneliti temukan selama melakukan penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Dalam pelaksanaan penelitian, terkadang area yang sudah diolesi krim
EMLA mengalami kegagalan saat dilakukan pemasangan infus dan
harus dipindah ke area yang lain, sehingga memperlama waktu
penelitian.
2. Dalam menyampaikan teori, peneliti masih mengalami keterbatasan
dan belum sempurna dalam melakukan penelitian.
B. Analisa Univariat
1. Karakteristik resonden
Responden di dalam penelitian ini berjumlah 40 orang anak usia
prasekolah yang terbagi atas 2 kelompok yaitu kelompok intervensi
62
yang diberikan EMLA dan kelompok kontrol yang tidak diberikan
EMLA. Masing-masing kelompok berjumlah 20 orang anak dan
berasal dari ruang anak yang sama.
a. Jenis kelamin
Jenis kelamin anak dalam penelitian ini adalah kelompok
intervensi berjenis kelamin laki-laki yaitu 60 %, sedangkan pada
kelompok kontrol 55 % responden berjenis kelamin perempuan.
Hasil analisis antara jenis kelamin terhadap tingkat nyeri bahwa
tidak terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap tingkat nyeri anak
usia prasekolah yang dilakukan pemasangan infus. Hasil
penelitian ini didukung oleh pendapat Gill (1990 dalam Potter dan
Perry, 2005) yaitu pengaruh jenis kelamin terhadap nyeri belum
dapat dijawab secara pasti. Toleransi terhadap nyeri dipengaruhi
oleh faktor-faktor biokimia yang merupakan hal unik pada setiap
individu tanpa memperhatikan jenis kelamin.Secara umum pria
dan wanita tidak berbeda secara signifikan dalam berespon
terhadap nyeri.
b. Kehadiran keluarga
Responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki
dukungan keluarga yang baik, hal ini terbukti dengan adanya
kehadiran keluarga baik pada kelompok kontrol maupun
63
kelompok intervensi yang masing-masing berjumlah 85 %. Hal ini
menunjukkan bahwa dukungan keluarga meliputi dukungan yang
diperoleh dari semua anggota keluarga baik ibu/bapak,
kakek/nenek, dan anggota keluarga lain.
Kehadiran keluarga/orang tua sangat penting bagi anak-anak yang
sedang mengalami nyeri. Kehadiran keluarga/orang tua pada
pelaksanaan prosedur tindakan tidak hanya berdampak
memberikan kenyamanan sehingga anak merasa lebih tenang dan
nyeri berkurang serta mau bekerja sama dalam prosedur tindakan,
namun anak juga merasa lebih nyaman dalam mengekspresikan
stressnya ketika didampingi oleh keluarganya/orang tuanya.
Kehadiran orang/keluarga yang dicintai akan meminimalkan
kesepian dan ketakutan. Apabila tidak ada keluarga atau
teman,seringkali pengalaman nyeri membuat seseorang semakin
tertekan. Kehadiran orang tua sangat penting bagi anak yang
sedang mengalami nyeri (Fein, 2004).
c. Ketakutan
Berdasar hasil uji statistik menunjukkan bahwa kelompok
intervensi 55 % anak tidak mengalami ketakutan saat dilakukan
prosedur pemasangan infus dilaksanakan.Sedangkan pada
kelompok kontrol 70 % anak mengalami ketakutan saat
dilakukan prosedur pemasangan infus dilakukan. Demikian secara
64
keseluruhan baik responden pada kelompok intervensi maupun
kelompok kontrol ketakutan saat dilakukan prosedur pemasangan
infus.
Ketakutan akan cidera dan nyeri tubuh terjadi pada rata-rata anak.
Konflik psikoseksual pada kelompok anak usia prasekolah
menurut Hockenberry & Wilson (2007) membuat anak sangat
rentan terhadap ancaman cedera tubuh. Ketakutan anak terhadap
perlukaan muncul karena anak menganggap tindakan dan prosedur
baik yang menimbulkan nyeri maupun yang tidak, merupakan
ancaman bagi integritas tubuhnya.
Ketakutan pada anak usia prasekolah terhadap prosedur tindakan
juga disebabkan anak usia prasekolah berada pada tahap
imaginasi. Cara berpikir magis menyebabkan anak usia prasekolah
memandang penyakit sebagai suatu hukuman.Bagi anak usia
prasekolah, hospitalisasi merupakan pengalaman baru dan sering
membingungkan yang dapat membawa dampak negatif terhadap
perkembangan normal. Hospitalisasi membuat anak masuk dalam
lingkungan yang asing, dimana anak biasanya dipaksa untuk
menerima prosedur yang menakutkan, nyeri tubuh dan
ketidaknyamanan (Muscari, 2005).
Karasch (2003) mengatakan bahwa rasa takut yang dirasakan anak
usia prasekolah sangat mendominasi karena hal tersebut
65
menimbulkan stress pada saat anak mengalami hospitalisasi. Yang
ditakutkan anak adalah tindakan invasif, takut terpisah dengan
orang tua dan ketidaknyamanan. Hal ini disebutkan juga oleh
Benini, Trapanotto, Gobber, Agosto , Carli , Srigo (2004) bahwa
anak yang mengalami ketakutan akan mengalami peningkatan
skala nyeri, mendemonstrasikan emosi yang negatif, mengalami
keterbatasan bicara, dan mengungkapkan ekspresi dalam reaksi
terhadap stimulus nyeri.Hamilton (2008) menyatakan bahwa 10%
dari seluruh anak memiliki rasa takut terhadap jarum, hal tersebut
menyebabkan anak menghindari pelayanan kesehatan.
Selanjutnya Hockenberry & Wilson (2007) juga menyebutkan
bahwa gangguan prosedur, rasa sakit atau tanpa sakit, adalah
ancaman bagi anak usia prasekolah, dimana konsep integritas
tubuh masih sedikit berkembang. Sedangkan perkembangan body
image berkembang mengikuti perkembangan kognitif dan
kemampuan berbahasa. Berdasarkan kondisi inilah pada umumnya
perasaan takut anak usia prasekolah lebih dominan dibandingkan
dengan periode usia lain.
d. Pengalaman pemasangan infus sebelumnya
kelompok intervensi 95 % anak sudah pernah mengalami prosedur
pemasangan infus sebelumnya, sedangkan pada kelompok kontrol
75 % anak sudah pernah mengalami prosedur pemasangan infus
66
sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden
pada kedua kelompok sudah pernah mengalami prosedur
pemasangan infus sebelumnya. Pengalaman sebelumnya dapat
memberikan gambaran pada anak terhadap apa yang akan
dialaminya sehingga akan mempengaruhi respon anak.
2. Tingkat nyeri
proporsi pada kelompok intervensi yang mengalami nyeri tertinggi
35 % ( n= 7), yaitu pada tingkat nyeri tidak dirasakan oleh anak.
Proporsi pada kelompok kontrol yang tertinggi 60 % ( n= 12 ) yaitu
pada tingkat nyeri sekali dan anak menjadi menangis. Hasil uji statistik
didapatkan p value 0,00, maka dapat disimpulkan ada perbedaan yang
signifikan rata-rata tingkat nyeri antara anak usia prasekolah yang
diberikan EMLA saat dilakukan pemasangan infus dengan anak usia
prasekolah yang tidak diberikan EMLA saat dilakukan pemasangan
infus.
Kondisi tersebut didukung dengan adanya teori yang mengatakan bahwa
dengan pemberian anestesi topikal (EMLA) pada pemasangan infus
dapat mengeblok impuls nyeri (Olson, 2003). Krim EMLA merupakan
suatu anestesi topikal yang terdiri dari campuran lidokain 2,5 % dan
prilokain 2,5 % yang bekerja dengan menurunkan permeabilitas
membran sel terhadap ion natrium dan mengaktivasi saraf berserat besar
delta A, sehingga akan menghambat impuls nyeri dan potensial aksi
67
tersebut berkurang dijalarkan ke fase berikutnya yang berakibat persepsi
nyeri tidak ada atau berkurang muncul di otak (Olson, 2003). Dengan
tidak adanya atau berkurangnya persepsi nyeri di otak berarti anak tidak
merasakan sakit ketika dilakukan pemasangan infus sehingga dapat
menunjukkan intensitas nyeri pada skala yang rendah.
Keadaan tersebut juga didukung dengan adanya penelitian yang pernah
dilakukan pada tahun 2002 di Amerika, dilaporkan bahwa dari 57 pasien
anak usia 8 tahun, 29 diberi plasebo dan 28 diberi EMLA 45 menit
sebelum insersi intra vena. Hasil penelitian tersebut menunjukkan
bahwa terdapat penurunan intensitas nyeri yang signifikan pada
pemberian EMLA sebelum insersi intra vena (Taylor, 2002).
C. Analisa Bivariat
1. Perbedaan rata-rata skor nyeri anak usia prasekolah yang dilakukan
pemasangan infus terhadap pemberian EMLA pada kelompok
intervensi dan kelompok kontrol.
Rata-rata tingkat nyeri anak usia prasekolah yang diberikan EMLA saat
dilakukan pemasangan infus adalah 1,20, sedangkan tingkat nyeri anak
usia prasekolah yang tidak diberikan EMLA saat dilakukan pemasangan
infus adalah 4,55. Ada perbedaan yang signifikan rata-rata tingkat nyeri
antara anak usia prasekolah yang diberikan EMLA saat dilakukan
pemasangan infus dengan anak usia prasekolah yang tidak diberikan
EMLA saat dilakukan pemasangan infus.
68
2. Pengaruh pemberian EMLA terhadap tingkat nyeri anak usia
prasekolah yang dilakukan pemasangan infus.
Hasil analisis menunjukkan bahwa 90 % anak usia prasekolah yang
diberikan EMLA saat dilakukan pemasangan infus mengalami nyeri
ringan. Sedangkan anak usia prasekolah yang tidak diberikan EMLA saat
dilakukan pemasangan infus sebanyak 5 % anak mengalami nyeri
ringan.Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa EMLA memberikan
pengaruh terhadap tingkat nyeri anak usia prasekolah yang dilakukan
prosedur pemasangan infus di rumah sakit.
Kondisi tersebut didukung dengan adanya teori yang mengatakan bahwa
dengan pemberian anestesi topikal (EMLA) pada pemasangan infus dapat
mengeblok impuls nyeri (Olson, 2003). Krim EMLA merupakan suatu
anestesi topikal yang terdiri dari campuran lidokain 2,5 % dan prilokain
2,5 % yang bekerja dengan menurunkan permeabilitas membran sel
terhadap ion natrium dan mengaktivasi saraf berserat besar delta A,
sehingga akan menghambat impuls nyeri dan potensial aksi tersebut
berkurang dijalarkan ke fase berikutnya yang berakibat persepsi nyeri
tidak ada atau berkurang muncul di otak (Olson, 2003). Dengan tidak
adanya atau berkurangnya persepsi nyeri di otak berarti anak tidak
merasakan sakit ketika dilakukan pemasangan infus sehingga dapat
menunjukkan intensitas nyeri pada skala yang rendah.
Keadaan tersebut juga didukung dengan adanya penelitian yang pernah
dilakukan pada tahun 2002 di Amerika, dilaporkan bahwa dari 57 pasien
69
anak usia 8 tahun, 29 diberi plasebo dan 28 diberi EMLA 45 menit
sebelum insersi intra vena. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
terdapat penurunan intensitas nyeri yang signifikan pada pemberian
EMLA sebelum insersi intra vena(Taylor, 2002).
70
BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan analisis dari hasil pembahasan, maka dikemukakan beberapa
kesimpulan dan saran sebagai berikut :
A. Kesimpulan
1. Gambaran karakteristik responden yang dilakukan pemasangan infus
di Ruang Anak Gedung A RSCM Jakarta pada kelompok intervensi
sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, sedangkan pada kelompok
kontrol sebagian besar berjenis kelamin perempuan. Sebagian besar
responden didampingi oleh orang tua/ keluarga saat dilakukan tindakan
dan umumnya responden ketakutan saat dilakukan tindakan serta
sebagian besar responden pada kedua kelompok sudah pernah
mengalami prosedur pemasangan infus sebelumnya.
2. Ada perbedaan yang signifikan tingkat nyeri anak usia prasekolah
yang diberikan EMLA saat dilakukan pemasangan infus dengan anak
usia prasekolah yang tidak diberikan EMLA saat dilakukan
pemasangan infus, dengan p value 0,00.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa 90 % anak usia prasekolah yang
diberikan EMLA saat dilakukan pemasangan infus mengalami nyeri
ringan. Sedangkan anak usia prasekolah yang tidak diberikan EMLA
71
saat dilakukan pemasangan infus sebanyak 5 % anak mengalami nyeri
ringan.
4. Ada pengaruh pemberian EMLA terhadap tingkat nyeri anak usia
prasekolah yang dilakukan pemasangan infus, dengan p value 0,00
dan OR = 18,00, artinya anak yang diberi EMLA 18 kali akan
mengalami nyeri ringan dibanding anak yang tidak diberi EMLA.
B. Saran
1. Bagi institusi pelayanan keperawatan
Pemberian EMLA pada prosedur pemasangan infus untuk anak usia
prasekolah ini diketahui merupakan salah satu managemen nyeri
farmakologis, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan oleh perawat
sebagai pilihan tindakan keperawatan dalam memberikan asuhan
keperawatan pada anak.
2. Bagi ilmu keperawatan
Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan manfaat
dalam menambah pengetahuan dan wawasan perawat mengenai
managemen nyeri farmakologis yang efisien dan efektif pada anak
yang dilakukan prosedur invasif, sehingga tindakan atraumatic care
bisa dilaksanakan di berbagai tingkat layanan kesehatan.
72
3. Bagi penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk penelitian
lebih lanjut pada penelitian serupa dan faktor-faktor yang
mempengaruhi keefektifan pemberian EMLA pada anak yang
dilakukan tindakan invasif. Peneliti merekomendasikan untuk
dilakukan penelitian sejenis dengan menggunakan observer di luar
peneliti dan dukungan fasilitas untuk intervensi, sehingga validitas
hasil penelitian lebih optimal. Penelitian berikutnya perlu dilakukan
dengan menggunakan pengambilan sampel lebih banyak dengan
sistem random sampling dan waktu lebih lama, pada tindakan invasif
lainnya dengan alat ukur yang lain sesuai tingkat usia anak.
DAFTAR PUSTAKA
Anonym.(2005) Pain and why it hurts. Http: //www.Faculty. Washington, edu/Chudler/Pain. Html. diakses tanggal 3 Desember 2012.
Ball, J.W.& Blinder, R.C. (2003).Pediatric care of children : Principle & practise. (
3rd edition ).St.Louis : Saunders Elsevier. Coyne, I. (2006).Children experiences of hospitalization.journal of child health care,
10 (4),326-336. Craven, R.F. & Hirnle, C.J.(2002). Fundamental of nursing: Human health and
function 3 rd ed. Philadelphia: Lippincott Dempsey, P.A., Dempsey, A.D, (2002).Riset keperawatan: Buku ajar dan
latihan.Edisi 4 ( Palupi Widyastuti.Penerjemah ).Jakarta : EGC. Fein J.A, Ganesh J,Alpern E.R, (2004).Medical staff attitudes towards family
presence during pediatric procedures.Pediatr Emerg Care; 20:224. Fortier, A.N., Anderson, C.T., (2009).Ethnicity matters in the assessment and
treatment of children’s pain.http://www.pediatric.org diperoleh tanggal 1 Maret 2010.
Hockenberry, M.J., & Wilson, D.(2007).Wong’s nursing care of infants and
children.( 8th ed ).St.Louis: Mosby Elsevier. Kozier, B.(2004). Fundamental of nursing: Concepts, proces, and practice. USA:
Pearson Prentice Hall. Nursalam. (2003). Konsep & penerapan metodologi penelitian ilmu keperawatan:
pedoman skripsi, tesis dan instrumen penelitian. Jakarta: Salemba Medika Olson, J.(2003). Belajar mudah farmakologi. Alih bahasa: Linda Chandranata.
Jakarta: EGC Potter, P.A., & Perry, A.G. (2005 ).Fundamental of nursing : Concepts, process, and
practice.( 4th ed. ).St.Louis: Mosby-Year Book, Inc. Reis & Holubcov.(2002). A Cooling spray ( Fluori-Methane ) reduces Immunization
Injection Pain. Http: // www 3. Us. Elsevier Health. Com/wow/PU032 html. diakses tanggal 28 Desember 2012
Sastroasmoro, S., & Ismael, S.I. (2008).Dasar-dasar metodologi penelitian
klinis.(Edisi 3).Jakarta : Sagung Seto.
Smeltzer, S.C. & Bare, B.G.(2002). Buku ajar keperawatan medikal bedah brunner & suddarth. Alih Bahasa: Agung Waluyo. Jakarta : EGC
Sugiyono.( 2008 ).Metode penelitian pendidikan.Bandung:Alfabeta. Supartini, Y.(2004). Buku ajar konsep dasar keperawatan anak. Jakarta: EGC. Taylor, A. (2002). EMLA reduces pain during intravenous catheter insertion in the
pediatric patient. Http: // www 3. Us Elsevier Health. Com/wow/Faces 21 Taylor. Html. diakses tanggal 28 Desember 2012.
Wahyuningsih, (Ed) (2007).Konsep dan penatalaksanaan nyeri,Cetakan I.Jakarta :
EGC. Wong.D.L., & Hockenberry, M.J. (2006).Nursing care of infants and children. ( 7th
edition ).St.Louis: Mosby. Wong, D.L. dkk.(2005). The validity, reliability, and preference of the Wong-Baker
FACES pain rating scale among Chinese, Japanese, and Thailan children. Http: // www 3. Us. Elsevier Health. Com/wow/0P020. html. diakses tanggal 28 Desember 2012.
Wong, D.L.(2003). Pedoman klinis keperawatan pediatrik. Alih bahasa: Monica
Ester. Jakarta: EGC Wong, D.L.(2002). Beyond first do no harm: principle of traumatic care. Http: //
www 3. Us. Elsevier Health. Com/wow/0P22022a. Html. diakses tanggal 28 Desember 2012.
Zempsky,T.W.,Joseph P.C & Committee on Pediatric Emergency, (2004).Relief of
pain and anxiety in pediatric in emergency medical systems.medicine, and section on anesthesiology and pain medicine.Pediatrics,114, 1348-1356.
INSTRUMEN PENGUKURAN NYERI
Nama Responden : __________________________ Tanggal : _____________________
Wong – Baker FACES Pain Rating Scale
Penjelasan Faces Rating Scale yaitu :
1. Nilai 0 : nyeri tidak dirasakan oleh anak
2. Nilai 1 : nyeri dirasakan sedikit saja
3. Nilai 2 : nyeri agak dirasakan oleh anak
4. Nilai 3 : nyeri yang dirasakan anak lebih banyak
5. Nilai 4 : nyeri yang dirasakan anak secara keseluruhan
6. Nilai 5 : nyeri sekali dan anak menjadi menangis
PROSEDUR PEMASANGAN INFUS
DENGAN PEMBERIAN EMLA
A. Pengertian
Pemasangan infus dengan pemberian EMLA adalah mengoleskan krim
EMLA pada tempat pemasangan infus dan menunggunya selama 60 menit
sebelum dipasang infus.
B. Tujuan
Tujuannya adalah sebagai tindakan pengobatan dan untuk mencukupi
kebutuhan tubuh akan cairan dan elektrolit dengan meminimalkan rasa
trauma pada anak.
C. Indikasi
Dilakukan pada: pasien dengan dehidrasi, pasien sebelum tranfusi darah,
pasien pra dan pascabedah sesuai dengan program pengobatan, pasien yang
tidak bisa makan dan minum melalui mulut serta pada pasien yang
memerlukan pengobatan yang pemberiannya harus dengan cara infus.
D. Persiapan
1. Alat
Alat yang harus dipersiapkan meliputi :
a. Krim EMLA ( sepertiga dari kemasan 5 gram )
b. Hipafik secukupnya
c. Alat tulis ( bollpoin )
d. Seperangkat infus set steril
e. Cairan yang diperlukan
f. Spuit, jarum dan kasa betadin steril dalam tempatnya
g. Kapas alkohol, plester, gunting verban, pembalut atau verban
h. Bengkok
i. Standar infus lengkap dengan gantungan botol
j. Perlak kecil dan alasnya, serta
k. Spalk dalam keadaan siap pakai bila perlu.
2. Pasien
a. Lakukan pendekatan kepada anak dan keluarga dengan
memberikan penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan
dengan bahasa yang sederhana.
b. Jelaskan pada anak bahwa krim EMLA adalah seperti krim ajaib
yang dapat menghilangkan rasa nyeri.
c. Anjurkan orang tua untuk mendampingi anak selama prosedur
dilakukan.
E. Pelaksanaan
1. Bersihkan permukaan kulit yang akan dipasang infus dan oleskan
lapisan tebal EMLA ( sepertiga dari kemasan 5 gram ).
2. Tempatkan balutan hipafik di atas krim EMLA dan beri label pada
balutan tentang tanggal dan waktu pemakaian EMLA.
3. Biarkan EMLA pada kulit selama 60 menit.
4. Perlak dan alasnya diletakkan di bawah anggota tubuh yang akan
dipasang infus.
5. Lepaskan balutan hipafik dengan kapas alkohol dan usap krim dari
kulit.
6. Observasi warna kulit terhadap kepucatan atau kemerahan, gores sedikit
kulit dan tanyakan pada anak apakah kulit merasakan sakit atau tidak (
untuk memastikan efek dari obat ). Bila tidak ada reaksi yang nyata,
pemberian krim EMLA dapat diulangi ( bila perlu ).
7. Botol cairan digantungkan pada standar.
8. Tutup botol cairan didesinfeksi dengan kapas alkohol lalu tusukkan
slang saluran udara dan saluran infus.
9. Tutup jarum dibuka cairan dialirkan sampai keluar sehingga tidak ada
udara dalam slang saluran infus kemudian diklem dan jarum ditutup
kembali ( tabung tetesan jangan sampai penuh ).
10. Lengan pasien bagian atas dibendung dengan karet pembendung,
daerah permukaan kulit yang akan ditusuk didesinfeksi lalu jarum
ditusukkan ke vena dengan lubang jarum menghadap ke atas.
11. Bila darah keluar pembendungan dilepaskan dan klem dibuka untuk
melihat kelancaran tetesan.
12. Bila tetesan lancar pangkal jarum direkatkan pada kulit dengan plester
kemudian tetesan diatur.
13. Jarum dan tempat tusukan ditutup dengan kain kasa betadin steril dan
diplester.
14. Atur posisi agar jarum infus tidak bergerak atau berubah posisi, bila
perlu gunakan spalk.
15. Pasien dirapikan dan atur posisi senyaman mungkin.
16. Tanyakan pada anak tentang intensitas nyeri yang dialami.
17. Peralatan dibersihkan dan dikembalikan ke tempat semula.
18. Bila pemberian infus selesai infus dihentikan, plester dilepas dan jarum
dicabut, bekas tusukan ditekan dengan kapas alkohol kemudian ditutup
dengan kasa steril dan diplester.
F. Perhatian
Yang perlu diperhatikan pada tindakan pemasangan infus antara lain :
1. Kelancaran cairan dan ketepatan jumlah cairan.
2. Bila terjadi bengkak, hematom dan lain-lain pada tempat pemasangan
infus, maka infus harus dihentikan dan pemasangannya dipindah ke
bagian lain.
3. Perhatikan reaksi selama 15 menit pertama. Bila timbul reaksi alergi,
perlambat
tetesan, bila perlu hentikan dan laporkan pada penanggung jawab.
4. Buat catatan pemberian infus secara rinci yang meliputi :
a. Tanggal, hari dan jam dimulainya pemasangan infus
b. Macam dan jumlah cairan serta jumlah tetesan per menit
c. Keadaan umum pasien ( tensi, nadi, pernafasan) selama pemberian
infus
d. Reaksi pasien yang timbul selama pemberian cairan
e. Nama dokter dan penanggung jawab
5. Perhatikan teknik septik dan aseptik.
6. Pemberian krim EMLA tidak boleh diberikan pada pasien usia di
bawah satu bulan, bayi usia di bawah 12 bulan yang mendapatkan
pengobatan agen methemoglobin ( sulfonamid, fenobarbital,
asetaminofen ) dan pada pasien yang diketahui alergi terhadap
anestesi lokal jenis amida.