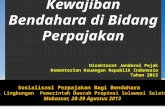TESIS PRAANGGAPAN DALAM PAMFLET SOSIALISASI ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of TESIS PRAANGGAPAN DALAM PAMFLET SOSIALISASI ...
TESIS
PRAANGGAPAN DALAM PAMFLET SOSIALISASIPELESTARIAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN WAKATOBI:
KAJIAN PRAGMATIK
PRESUPPOSITIONS IN THE SOCIALIZATION PAMPHLETOF ENVIRONMENTAL CONSERVATION IN WAKATOBI
REGENCY: A PRAGMATIC STUDY
KARIM
PROGRAM STUDI BAHASA INDONESIAFAKULTAS ILMU BUDAYA
SEKOLAH PASCASARJANAUNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR2017
PRAANGGAPAN DALAM PAMFLET SOSIALISASIPELESTARIAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN WAKATOBI:
KAJIAN PRAGMATIK
Tesis
Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
PROGRAM STUDI
BAHASA INDONESIA
Disusun dan diajukan oleh
KARIM
Kepada
SEKOLAH PASCASARJANAUNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR2017
v
PRAKATA
Puji syukur patut dipanjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah
memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga tesis
yang berjudul “Praanggapan dalam Pamflet Sosiaalisasi Pelestarian
Lingkungan di Kabupaten Wakatobi: Kajian Pragmatik” ini dapat
diselesaikan dengan baik. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan
kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan
para sahabatnya. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Bahasa
Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak
ditemui hambatan. Akan tetapi, berkat bantuan dari berbagai pihak
sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu,
melalui lembaran ini, penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada:
1. Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U., selaku ketua komisi penasihat dan
kepada Dr. Hj. Asriani Abbas, M.Hum., sebagai ketua Program Studi
Magister Bahasa Indonesia dan selaku anggota komisi penasihat yang
telah memberikan bimbingan secara bertahap dan penuh kesabaran
sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
vi
2. Dr. Gusnawaty, M.Hum, Dr. Hj. Ery Iswary, M.Hum., dan Dr. Munira
Hasjim, M.Hum., atas segala saran dan kritikan yang konstruktif untuk
penyelesaian tesis ini;
3. kedua orang tua penulis, yaitu ayahanda La Hiri dan ibunda Haliana,
yang telah mencurahkan kasih sayang yang tidak ternilai harganya
sejak penulis dilahirkan hingga saat ini. Semoga keduanya selalu
dilimpahkan rahmat dan kesehatan dari Allah Swt. dan dipanjangkan
umur mereka;
4. kakak-kakak penulis, Hariyanto, S.H., bersama istri Merry Handayani,
Dinarti, S.Pd., bersama suami Muhammad Yunus, S.Pd., yang telah
memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis untuk selalu
sabar dalam menjalani studi. Semoga mereka selalu diberikan oleh
Allah Swt. kesehatan, panjang umur, rezeki yang cukup;
5. Rizki Sasmala, S. Farm., Apt., sebagai sosok yang selama
penyelasaian studi selalu memotivasi dan percaya setiap keputusan
yang diambil penulis;
6. sahabat seperjuangan penulis di Program Studi Magister Bahasa
Indonesia, A. Aryana, M. Nawir, Sumiaty, Susiati, Risman, Taufik, A.
Yusdianti, Harziko, Sutrisno, Asrifal K., Raviqa, Rima, Nur Rahma Al-
Haqq, dan Nur Sariati yang tak henti-hentinya memberikan semangat
kepada penulis;
vii
7. rekan-rekan Magister Linguistik dan English Leanguage Study
program Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang selalu
memberikan dukungan selama proses penyelesaian tesis ini;
8. Pak Nadir Ladjamudi, M.Pd., yang tak henti-hentinya memotivasi dan
menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan studi;
9. Pak Muhtar, Pak Mullar, dan Daeng Nai yang selalu membantu dalam
pengurusan administrasi dan teknis selama menempuh pendidikan di
Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas
Hasanuddin;
10.seluruh dosen dan staf pegawai Program Magister Bahasa Indonesia
Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu dan bantuan
dengan tulus kepada penulis selama ini.
Pada proses penulisan tesis ini, penulis menghadapi banyak
masalah dan hasilnya mungkin kurang sempurna. Oleh karena itu, penulis
mohon maaf atas semua kekurangan di dalam penulisan ini. Saran dan
kritikan dari semua pihak yang sifatnya membangun demi penyempurnaan
tesis ini, sangat penulis harapkan. Penulis berharap tesis ini dapat
bermanfaat bagi para pembaca dan bermanfaat bagi pengembangan
bahasa Indonesia yang lebih baik pada masa yang akan datang.
Makassar, Oktober 2017
Penulis
viii
ABSTRAK
KARIM. Praanggapan dalam Pamflet Sosialisasi Pelestarian Lingkungandi Kabupaten Wakatobi: Kajian Pragmatik (dibimbing oleh TadjuddinMaknun dan Asriani Abbas).
Penelitian ini bertujuan: (1) menjelaskan jenis praanggapan danbentuk kalimat dalam pamflet sosialisasi pelestarian lingkungan diKabupaten Wakatobi; (2) menguraikan penggunaan praanggapan, jeniskalimat dan maksud kalimat pada tiap-tiap penerbit pamflet sosialisasipelestarian lingkungan di kabupaten Wakatobi.
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang mengkaji fenomenapraanggapan dengan pendekatan pragmatik. Data berupa data tulis yangbersumber dari pamflet sosialisasi pelestarian lingkungan di KabupatenWakatobi khususnya Kecamatan Wangi-wangi dan sekitarnya. Datadikumpulkan menggunakan metode simak melalui teknik rekam dan catat.Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) praanggapan yangterdapat dalam pamflet sosialisasi pelestarian lingkungan di KabupatenWakatobi terdiri atas praanggapan eksistensial, praanggapan faktif,praanggapan struktural, dan praanggapan konterfaktual. Adapun jeniskalimat yang digunakan pada pamflet sosialisasi pelestarian lingkungan diKabupaten Wakatobi terdiri atas deklaratif, interogatif, imperatif, danekslamatif sedangkan maksud pengutaraannya untuk memerintah danmenginformasikan; dan (2) Pengunaan praanggapan dan bentuk kalimatpada setiap penerbit pamflet sosialisasi pelestarian lingkungan diKabupaten Wakatobi jika dibandingkan antara Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM) dan pemerintah, LSM lebih dominan menggunakanpraanggapan eksistensial berbentuk kalimat deklaratif sedangkanpemerintah menggunakan praanggapan faktif berbentuk imperatif.
Kata kunci: praanggapan, kalimat, pamflet pelestarian lingkungan,wakatobi
ix
ABSTRACT
KARIM. Presuppositions in the Socialization Pamphlet of EnvironmentalConservation in Wakatobi Regency: a Pragmatic Study (supervised byTadjuddin Maknun and Asriani Abbas).
This research aimed (1) to explain the types of presuppositions andsentence form in the pamphlet socialization of environmental conservationin Wakatobi Regency; (2) describes the use of presuppositions, sentencetypes and sentence meanings in each publisher of environmentalconservation pamphlet in Wakatobi Regency.
This research is a qualitative descriptive character that examinesthe phenomenon of pre-awareness with pragmatic approach. Data in theform of written data originating from pamphlets pamphlet socialization ofenvironmental conservation in Wakatobi Regency, especially DistrictWangi-Wangi and surrounding areas. Data were collected usingobservation method through tapping technique and record. Data wereanalyzed descriptively qualitative.
The results showed that: (1) the presuppositions contained in theenvironmental conservation pamphlet in Wakatobi District consisted ofexistential prejudices, factive presumptions, structural presuppositions,and counterfactual presuppositions. The types of sentences used in thepamphlet socialization of environmental conservation in WakatobiRegency consists of declarative, interrogative, imperative, and ekslamatifwhile the intention to rule and inform; and (2) The use of presuppositionsand sentence types in each publisher of environmental conservationpamphlet in Wakatobi Regency when compared between NGOs andgovernment, NGOs are more dominant to socialize environmentalconservation in Wakatobi Regency compared with the government.
Keywords: presuppositions, sentences, pamphlets of environmentalconservation, Wakatobi Regency
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................i
HALAMAN PENGAJUAN............................................................................ ii
HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .............................................vi
PRAKATA ...................................................................................................v
ABSTRAK ................................................................................................ viii
ABSTRACT................................................................................................ ix
DAFTAR ISI ................................................................................................x
DAFTAR TABEL .........................................................................................x
DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL....................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN.............................................................................. 1
A. Latar Belakang ................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah .......................................................................... 9
C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 9
D. Manfaat Penellitian.......................................................................... 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA................................................................... 11
A. Hasil Penelitian yang Relevan....................................................... 11
B. Landasan Teori ............................................................................. 15
1. Pragmatik................................................................................. 15
2. Pengertian Praanggapan ......................................................... 18
3. Pemerolehan Praanggapan ..................................................... 23
4. Jenis-jenis Praanggapan ......................................................... 26
xi
a. Praanggapan Eksistensial .................................................. 27
b. Praanggapan Faktif ............................................................ 28
c. Praanggapan Leksikal ........................................................ 29
d. Praanggapan Nonfaktif ....................................................... 29
e. Praanggapan Struktural...................................................... 30
f. Praanggapan Konterfaktual ................................................ 31
5. Bentuk Kalimat dan Maksud .................................................... 32
a. Kalimat Deklaratif ............................................................... 33
b. Kalimat Interogatif............................................................... 35
c. Kalimat Imperatif................................................................. 37
d. Kalimat Ekslamatif .............................................................. 38
6. Pengertian Pamflet .................................................................. 39
C. Kerangka Pikir............................................................................... 43
D. Definisi Operasional ...................................................................... 44
BAB III METODE PENELITIAN................................................................ 45
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .................................................. 45
B. Sumber Data dan Jenis Data ........................................................ 45
C. Lokasi dan Waktu Penelitian ......................................................... 46
D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data ........................................ 46
E. Teknik Analisis Data...................................................................... 47
BAB IV HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN................................... 49
A. Praanggapan dan Bentuk Kalimat Pada Pamflet Sosialisasi
pelestarian Lingkungan di Kabupaten Wakatobi ........................... 49
xii
1. Praanggapan Eksistensial ....................................................... 50
2. Praanggapan Faktif.................................................................. 70
3. Praanggapan Leksikal ............................................................. 83
4. Praanggapan Struktural ........................................................... 85
5. Praanggapan Konterfaktual ..................................................... 91
B. Penggunaan Praanggapan, Bentuk Kalimat dan Maksud Kalimat
pada Tiap-tiap Penerbit Pamflet Sosialisasi Pelestarian Lingkungan
di Kabupaten Wakatobi ................................................................. 97
1. Lembaga Swadaya Masyarakat............................................... 97
2. Pemerintah .............................................................................. 99
3. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah .................. 100
BAB V PENUTUP .................................................................................. 102
A. Simpulan ..................................................................................... 102
B. Saran........................................................................................... 103
DAFTAR PUSTAKA............................................................................... 105
LAMPIRAN
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1. Penggunaan bentuk kalimat pada praanggapan eksistensial. 69
Tabel 4.1. Penggunaan bentuk kalimat pada praanggapan faktif.............83
Tabel 4.3. Penggunaan bentuk kalimat pada praanggapan leksikal.........85
Tabel 4.4. Penggunaan bentuk kalimat pada praanggapan struktural.....91
Tabel 4.5. Penggunaan bentuk kalimat pada praanggapan
konterfaktual.............................................................................96
Tabel 4.6. Rekapitulasi penggunaan praanggapan dan bentuk kalimat
pada pamflet yang diterbitkan LSM..........................................98
Tabel 4.7. Rekapitulasi penggunaan praanggapan dan bentuk kalimat
pada pamflet yang diterbitkan pemerintah...............................99
Tabel 4.8. Rekapitulasi penggunaan praanggapan dan bentuk kalimat
pada pamflet yang diterbitkan LSM dan
pemerintah..............................................................................100
xii
DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL
PE : Praanggapan Eksistensial
PF : Praanggapan Faktif
PL : Praanggapan Leksikal
PN : Praanggapan Nonfaktif
PS : Praanggapan Struktural
PK : Praanggapan Konterfaktual
Dek : Kalimat Deklaratif
Imp : Kalimat Imperatif
Int : Kalimat Interogatif
Eks : Kalimat Ekslamatif
+ : Ditemukan (positif)
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dewasa ini masalah lingkungan sering diperbincangkan.
Sebelumnya orang menduga masalah lingkungan lebih banyak
dipengaruhi faktor alam seperti iklim, yang mencakup temperatur, curah
hujan, kelembaban, dan tekanan udara. Belakangan mulai disadari bahwa
aktivitas manusia pun memengaruhi iklim dan lingkungan secara
signifikan. Sebagai contoh, penebangan hutan memengaruhi perubahan
suhu dan curah hujan secara lokal. Selain itu, penangkapan ikan
menggunakan alat tangkap tak ramah lingkungan seperti pukat harimau,
bom, bius, dan perburuan satwa langka yang berdampak terhadap
rusaknya ekosistem di perairan, baik terumbu karang maupun satwa
langka yang semakin berkurang. Aktivitas manusia semacam ini tentu saja
ada faktor yang melatarbelakanginya, misalnya motivasi ekonomi.
Hal yang memprihatinkan adalah rusaknya lingkungan akibat ulah
manusia. Pemerhati lingkungan sangat khawatir membayangkan bencana
besar yang akan melanda umat manusia akibat rusaknya lingkungan.
Kerusakan tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran tentang
pentingnya melestarikan lingkungan di tengah masyarakat. Di tengah
kondisi tersebut, upaya pelestarian lingkungan telah dilaksanakan baik
pembenahan lahan hijau di perkotaan, pengawasan terhadap pembukaan
lahan pertanian dan pertambangan, dan pembentukan taman nasional.
2
Khususnya taman nasional, Pemerintah Indonesia telah membentuk
sebanyak 50 Taman Nasional salah satunya adalah Taman Nasional
Wakatobi (TNW).
Berkenaan dengan hal tersebut, Kabupaten Wakatobi adalah
Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran dari Kabupaten Buton,
Sulawesi Tenggara pada tahun 2003. Seluruh wilayahnya merupakan
TNW yang terdiri dari 97% laut dan 3% darat. Berbagai penghargaan
yang diperoleh DOB ini antara lain: Green City Award dari Kementerian
Lingkungan Hidup pada tahun 2010, Penetapan Wakatobi sebagai Pusat
Biosfer Bumi dari UNESCO pada tahun 2012, dan sebagainya. Dalam hal
upaya pelestarian lingkungan, selain TNW juga gencar dilakukan
sosialisasi pelestarian lingkungan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Wakatobi, Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi, WWF-
Indonesia, The Nature of Confervation, dan berbagai Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) lokal lainnya. Upaya pendampingan khususnya kepada
nelayan berupa pelatihan-pelatihan kerap dilakukan. Tidak cukup sampai
disitu, lembaga-lembaga tersebut juga melakukan sosialisasi melalui
pamflet, baliho, dan spanduk yang tersebar di ruang-ruang publik.
Pamflet merupakan salah satu media yang efektif dan efisien.
Pamflet dinilai lebih efektif karena pembuat pamflet dapat menuliskan
gagasan atau ide yang ada dipikiran mereka secara bebas dan spontan
tanpa perlu memikirkan unsur seni tulis maupun unsur seni rupanya,
sedangkan dinilai lebih efisien karena tidak memakan banyak tempat dan
3
biaya. Adapun dalam pembuatannya, informasi dalam pamflet ditulis
dalam bahasa yang ringkas dan dimaksudkan agar mudah dipahami
dalam waktu singkat (Slametrianto, 2009: 1).
Pamflet sosialisasi pelestarian lingkungan di kabupaten wakatobi
dipilih karena berkenaan dengan isu-isu aktual, adanya perbedaan
dengan pamflet lainnya, yaitu pamflet pelestarian lingkungan di kabupaten
wakatobi diterbitkan oleh lembaga-lembaga nonprofit sedangkan pamflet
lainnya diterbitkan oleh lembaga-lembaga atau perorangan yang
berorientasi profit. Selain itu, konsekuensi dari pamflet pelestarian
lingkungan di Kabupaten Wakatobi akan berdampak pada harmonisnya
hubungan manusia dengan alam jika bahasa dalam pamflet tersebut
mampu memengaruhi dengan efektif. Isi pamflet hakikatnya hasil kontruksi
realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Berdasarkan
fungsinya, bahasa bukan saja sebagai alat merepresentasikan realitas,
namun juga bisa menentukan relief seperti apa yang diciptakan oleh
bahasa tentang realitas tersebut, dengan arti bahasa dalam pamflet
mempunyai kemampuan untuk berperan membentuk opini publik.
Akibatnya, pamflet memiliki peluang yang besar memengaruhi makna dan
gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksikan. Dengan kata
lain, dapat menciptakan peristiwa, menafsirkan dan mengarahkan
kebenaran.
Berkaitan dengan hal di atas, unsur bahasa sangat penting dalam
pamflet karena penggunaan bahasa tertentu dalam pamflet dapat
4
membantu petutur agar dapat merasakan dan memahami maksud yang
disajikan pamflet. Satuan bahasa tersebut dapat berupa rangkaian kata
atau ujaran, berbentuk tulis. Dalam peristiwa komunikasi secara tulisan,
dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antar penutur dan
petutur. Wacana tulis tersebut tidak hanya terpaku pada hal yang
disampaikan oleh penutur, namun juga konteks yang mengikuti dan
bagaimana pengaruhnya. Kadang-kadang makna wacana menjadi sulit
diterka karena pemahaman makna tersebut tidak hanya berasal dari
tuturan saja tetapi juga mesti ada pemahaman bersama antara penutur
dan petutur mengenai asumsi awal lahirnya tuturan. Sehingga untuk
memahami tuturan tersebut dapat diteliti praanggapannya.
Praanggapan diperoleh dari pernyataan yang disampaikan tanpa
perlu ditentukan apakah praanggapan tersebut benar atau salah.
Pemahaman mengenai praanggapan ini melibatkan dua partisipan utama,
yaitu penutur atau yang menyampaikan suatu pernyataan atau tuturan
dan lawan tutur dan biasanya diasosiasikan dengan pemilihan kata atau
diksi, frasa, dan struktur (Yule, 2014: 26). Gagasan Yule tersebut
memperlihatkan adanya indikasi terjadinya praanggapan yang aktual
ketika hal tersebut berkaitan dengan konteks dalam komunikasi.
Praanggapan dapat dikaji melalui dua kajian ilmu, yaitu Semantik dan
Pragmatik. Semantik merupakan kajian yang memaknai suatu tuturan
tanpa melihat adanya konteks. Adapun kajian pragmatik, makna tuturan
dikaji secara lengkap beserta konteks situasinya. Sehingga, untuk
5
mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang praanggapan
dibutuhkan pendekatan pragmatik. Hal ini perlu dilakukan mengingat
bahasa dalam pamflet para pengarang berusaha agar pesan yang
tertuang dalam pamflet dapat sampai kepada masyarakat.
Praanggapan hanya akan terjadi bila antara penutur atau penulis
dan petutur atau pembaca memiliki kesepemahaman (background
knowledge) yang sama. Jika keduanya tidak memiliki kesepehaman yang
sama, praanggapan tidak akan terjadi. Praanggapan digunakan dalam
suatu komunikasi atau wacana baik lisan maupun tulisan. Demikian pula
halnya dalam sebuah pamflet. Lahirnya sebuah pamflet tidak terlepas dari
penggunaan praanggapan. Oleh karena itu pembaca harus memahami
praanggapan untuk memahami maksud dalam sebuah pamflet tersebut.
Dalam memahami suatu bahasa yang dikaji menurut penuturnya,
tidak cukup hanya diklasifikasikan berdasarkan jenis praanggapannya
saja, tetapi juga harus bisa dipahami berdasarkan bentuk bahasa yang
digunakan dalam pamflet tersebut. Tujuannya agar diketahui maksud
tuturan tersebut. Bentuk bahasa yang digunakan dalam pamflet dapat
dilihat dari piranti linguistiknya yaitu: kata, frasa, dan kalimat.
Berikut ini contoh tuturan dalam pamflet sosialisasi pelestarian
lingkungan di Kabupaten Wakatobi.
Contoh (1)
Terumbu karang sehat, ikan berlimpah.
6
Konteks:Pamflet dipajang pada papan pusat informasi diperkampungan Bajo, Desa Mola, Kecamatan Wangi-wangiSelatan. Pamflet tersebut diterbitkan oleh LSM KomunitasMelihat Alam (Kamelia) Wakatobi.
Contoh (1) mencirikan jenis praanggapan eksistensial. Keberadaan
praanggapan eksistensial tidak hanya diasumsikan pada kalimat-kalimat.
Akan tetapi dapat lebih diperluas dengan mengidentifikasi keberadaan
sesuatu dalam sebuah tuturan. Penanda praanggapan eksistensial pada
contoh (1) merujuk pada satuan bahasa “terumbu karang”, yang
mengindikasikan keberadaan terumbu karang sebagai bagian dari
kehidupan masyarakat Bajo. Perlu diketahui bahwa masyarakat Bajo
dominan berprofesi sebagai nelayan sehingga pernyataan dalam kalimat
tersebut menyiratkan maksud bahwa terumbu karang dapat dibuktikan
keberadaannya. Jadi praanggapannya, yaitu “ada terumbu karang”.
Berdasarkan bentuk kalimat yang digunakan, maka contoh (1)
“terumbu karang sehat, ikan berlimpah” berbentuk kalimat deklaratif. Hal
ini tampak pada konten kalimat tersebut berupa pernyataan. Satuan
bahasa terumbu karang sehat dan ikan berlimpah merupakan pernyataan
hubungan sebab akibat. Artinya bahwa kalimat tersebut memberikan
informasi jika terumbu karang sehat maka berkonsekuensi terhadap
meningkatnya jumlah ikan. Merujuk pada konteks, maka contoh (1)
bermaksud memerintah masyarakat agar menjaga kelestarian terumbu
karang jika ingin mendapatkan ikan dalam jumlah besar.
7
Contoh (2)
Lobster, kepiting, dan rajungan dalam kondisi bertelur dilarangditangkap dan dijual.
Konteks: Lokasi pamflet di pasar ikan, Kelurahan Mandati III,Kecamatan Wangi-wangi Selatan. Pamflet tersebutditerbitkan oleh Pusat Penyuluhan Kelautan danPerikanan, Kemeterian Kelautan dan Perikanan RI (KKP).
Contoh (2) mencirikan jenis praanggapan faktif. Hal ini tampak
pada penggunaan kata kerja “dilarang” diikuti informasi yang
dipraanggapkan. Satuan bahasa “dilarang” bermakna memerintahkan
supaya tidak melakukan sesuatu sehingga dapat diasumsikan bahwa
sebelumnya masyarakat (nelayan) sering menangkap dan menjual lobster,
kepiting, dan rajungan dalam kondisi bertelur. Pemerolehan praanggapan
juga mengacu pada situasi pasar ikan yang ramai dikunjungi penjual dan
pembeli. Biasanya, penjual adalah para istri nelayan setempat. Oleh
karena itu, dapat dikatakan bahwa praanggapannya adalah “masyarakat
(nelayan) sering menangkap dan menjual lobster, kepiting, dan rajungan
dalam kondisi bertelur”.
Berdasarkan bentuk kalimat yang digunakan, maka contoh (2)
berbentuk kalimat imperatif. Hal ini tampak pada penggunaan satuan
lingual “dilarang” yang berarti perintah untuk tidak melakukan suatu
perbuatan. Jika merujuk pada konteks maka contoh (2) bermaksud
memerintah masyarakat agar tidak menangkap lobster, kepiting, dan
rajungan dalam kondisi bertelur.
8
Kedua contoh yang telah dideskripsikan dapat dicermati bahwa
tiap-tiap lembaga yang menerbitkan pamflet memiliki metode yang
berbeda dalam hal penyampaian informasi. Pada contoh (1), LSM Kamelia
menyampaikan kampanye pelestarian lingkungan dengan asumsi dasar
praanggapan eksistensial. Kemudian praanggapan ini direalisasikan
dengan menggunakan kalimat deklaratif yang dirmaksudkan untuk
memerintah. Artinya bahwa LSM menyampaikan pesan melalui pamflet
secara tak langsung. Lain halnya dengan contoh (2), penerbit pamflet
adalah pemerintah. Sebagai asumsi dasar lahirnya tulisan dalam pamflet,
yaitu praanggapan faktual. Kemudian praanggapan ini direalisasikan
dengan menggunakan kalimat imperatif yang dirmaksudkan untuk
memerintah. Artinya bahwa pemerintah menyampaikan pesan melalui
pamflet secara langsung.
Berkaitan dengan penjelasan yang telah dipaparkan menunjukkan
bahwa ada perbedaan penggunaan praanggapan dan bentuk kalimat
yang digunakan pada tiap-tiap penerbit pamflet. Hal tersebut disebabkan
oleh aspek di luar bahasa (makro) yang bersinggungan langsung dengan
bahasa, seperti pengetahuan bersama, konteks situasi, dan partisipan.
Sehingga penelitian ini menguraikan penggunaan praanggapan, bentuk
kalimat, dan maksud kalimat yang terdapat pada pamflet pada tiap-tiap
penerbit pamflet sosialisasi pelestarian lingkungan di Kabupaten
Wakatobi. Untuk memudahkan analisis penelitian ini maka peneliti
9
menitiberatkan pada analisis dan pendeskripsian kategori praanggapan
serta bentuk kalimat dalam lingkup kajian pragmatik.
B. Rumusan Masaalah
Berdasarakan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan
di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.
1. Jenis praanggapan dan bentuk kalimat apa saja yang terdapat pada
pamflet sosialisasi pelestarian lingkungan di Kabupaten Wakatobi?
2. Bagaimanakah penggunaan praanggapan, bentuk kalimat dan maksud
kalimat yang terdapat pada pamflet pada tiap-tiap penerbit pamflet
sosialisasi pelestarian lingkungan di Kabupaten Wakatobi?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, tujuan dalam
penelitian dapat dideskripsikan berikut ini.
1. Menjelaskan jenis praanggapan dan bentuk kalimat yang terdapat pada
pamflet sosialisasi pelestarian lingkungan di Kabupaten Wakatobi.
2. Menguraikan penggunaan praanggapan, bentuk kalimat, dan maksud
kalimat yang terdapat pada pamflet pada tiap-tiap penerbit pamflet
sosialisasi pelestarian lingkungan di Kabupaten Wakatobi.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis
maupun secara praktis.
10
1. Secara Teoretis
Secara teoretis, manfaat penelitian ini sebagai berikut:
a) pengembangan teori kebahasaan pada umumnya;
b) memberikan kontribusi teoretis dalam bidang pragmatik; dan
c) menambah khazanah ilmu bahasa terutama praanggapan.
2. Secara Praktis
Secara praktis, manfaat penelitian ini sebagai berikut:
d) pembaca dapat memahami tentang praanggapan dalam bahasa,
khususnya dalam pamflet;
e) menjadi bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji
mengenai masalah yang relevan dengan penelitian ini;
f) menjadi bahan perbandingan bagi penelitian kebahasaan
selanjutnya; dan
g) menjadi bahan rekomendasi kepada lembaga-lembaga terkait,
perihal peran pamflet sebagai sebagai media sosialisasi
pelestarian lingkungan di Kabupaten Wakatobi.
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian yang berhubungan dengan praanggapan sudah ditulis
oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Hafid (2012), Winarni (2015),
dan Siahaan (2015).
Hafid (2012) menulis tesis dengan berjudul “Ragam Bahasa Iklan
pada Media Cetak”. Dalam penelitiannya aspek yang dianalisisis yaitu:
tindak tutur, praanggapan, implikatur, bentuk pilihan kata, dan faktor-faktor
yang memengaruhi penggunaan ragam bahasa iklan. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa bentuk tindak tutur yang ditemukan pada iklan
berupa menetapkan atau menjelaskan, memerintahkan atau memohon,
dan berterima kasih. Bentuk praanggapan yang digunakan yaitu:
praanggapan eksistensial, faktif, dan struktural. Implikatur iklan dapat
membantu pembaca untuk mendapatkan suatu penjelasan yang tersirat
tentang sesuatu yang ditampilkan pengiklan sehingga pembaca dapat
memahami dan mengerti iklan sesuai konteks dan situasinya. Bentuk
pilihan kata yang ditemukan pada iklan berupa pilihan kata keterangan,
kata sifat, kata kerja, persona , ajakan, partikel konjungsi intrakalimat,
sinonim, kalimat interogatif, numeralia, kosakata dalam bahasa daerah
Makassar dan bahasa asing. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi
ragam bahasa pada iklan pada media cetak yaitu: adanya pengaruh
komponen tutur yang meliputi: (1) waktu dan situasi, (2) pihak yang terlibat
12
di dalam tuturan, (3) maksud dan tujuan tuturan, (4) bentuk dan isi ujaran,
(5) nada dan cara pesan disampaikan, (6) bahasa yang digunakan, (7)
norma atau aturan, (8) jenis bentuk penyampaian, (9) konteks, dan (10)
sasaran yang dituju sebuah iklan.
Relevansi penelitian yang dilakukan Hafid (2014) dengan penelitian
ini ada pada kajiannya, yaitu pragmatik. Perbedaannya selain terletak
pada objek kajiannya, juga pada prioritas aspek yang dianalisis. Hafid
menganalisisi aspek tindak tutur, praanggapan, implikatur, bentuk pilihan
kata, dan faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan ragam bahasa
iklan, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada analisis praanggapan
dan bentuk kalimat yang digunakan pada pamflet sosialisasi pelestarian
lingkungan di kabupaten Wakatobi dan objek kajiannya adalah teks pada
pamflet.
Penelitian yang berkaitan dengan praanggapan juga telah
dilakukan oleh Winarni (2015) dengan judul “Analisis Praanggapan
Pernyataan Humor dalam Stand Up Comedy Indonesia”. Penelitian ini
merumuskan jenis-jenis praanggapan yang muncul dalam pernyataan
humor dan kontribusi praanggapan dalam membantu terciptanya humor
pada Stand up comedy Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dihasilkan
olehnya, ditemukan jenis-jenis praanggapan yaitu: eksistensial sebanyak
184, faktual sebanyak 18, leksikal sebanyak 82, stuktural sebanyak 11,
nonfaktual sebanyak 3, dan kontrafaktual sebanyak 11. Jumlah
13
praanggapan yang muncul pada 20 pernyataan comic sebanyak 309
praanggapan.
Walaupun praanggapan eksistensial paling dominan, tidak menjadi
kontribusi utama dalam proses penciptaan humor dalam stand up comedy.
Hal ini disebabkan oleh praanggapan eksistensial hanya menyebutkan
entitas-entitas dalam pernyataan comic. Salah satu yang menjadi
penyebab praanggapan eksistensial sering muncul dalam stand up
comedy karena comic sebagai pelawak tunggal sering melibatkan dirinya
sendiri sebagai sebuah entitas yang dibicarakan dalam stand up comedy
dengan cara monolog.
Praanggapan leksikal juga merupakan jenis praanggapan yang
cukup banyak muncul dalam pernyataan humor comic dalam stand up
comedy Indonesia. Hal ini disebabkan oleh praangapan leksikal
menggunakan cara tersirat dalam menyampaikan materi humor. Cara
tersirat dalam menyampaikan pernyataan humor inilah yang memiliki
potensi lebih besar dalam menimbulkan efek lucu bagi penerima humor.
Praanggapan leksikal ini yang paling memiliki kontribusi dalam membantu
menciptakan humor dalam Stand up comedy Indonesia. Kontribusi
praanggapan leksikal ini dapat terlihat dalam proses kognitif, mekanisme
semantis, dan dari segi kontekstual.
Winarni menyimpulkan bahwa praanggapan leksikal memiliki
kontribusi yang sangat penting dalam pernyataan humor stand up comedy
Indonesia. Maka dari itu, dalam setiap pernyataan comic selalu muncul
14
praanggapan leksikal. Dalam stand up comedy sebuah pernyataan akan
dapat disebut lucu jika ada makna lain yang berbeda dan bertentangan
dengan yang disampaikan tersirat oleh comic. Bahkan, jenis praanggapan
lain yang muncul dalam pernyataan comic tidak akan dapat menciptakan
efek lucu jika tidak ada kemunculan praanggapan leksikal dalam
pernyataan yang sama.
Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Winarni (2015) dengan
penelitian ini adalah objek materialnya dan analisis terhadap jenis
praanggapan yang berkontribusi dalam pernyataan humor. Adapun,
dalam penelitiaan ini selain mendeskripsikan jenis-jenis praanggapan dan
bentuk kalimat, juga berusaha menjelaskan penggunaan praanggapan,
bentuk kalimat dan maksud kalimat yang terdapat pada pamflet pada tiap-
tiap penerbit pamflet (penutur) dalam menyampaikan pesan.
Penelitian yang berkaitan dengan praanggapan dengan objek
material berbeda, juga dilakukan oleh Siahaan (2015) dalam tesisnya
berjudul “Pemakaian Praanggapan pada Tuturan Wisatawan Asing dalam
Berinteraksi dengan Penduduk Setempat di Ubud, Bali”. Hasil penelitian
tersebut memperlihatkan bahwa terdapat tujuh jenis praanggapan yang
ditemukan dari lima belas peristiwa tutur yaitu; praanggapan eksistensial,
praanggapan faktual, praanggapan leksikal, praanggapan struktural,
praanggapan pengandaian, praanggapan implikatif, dan praanggapan
waktu. Praanggapan struktural merupakan praanggapan yang paling
dominan berperan dalam peristiwa tutur ini. Penelitian ini juga menemukan
15
sebuah pola pemakaian praanggapan dari ketiga variabel tersebut yakni
praanggapan struktural diikuti dengan praanggapan eksistensial.
Kemudian praanggapan leksikal. Pemahaman sebuah praanggapan
dalam sebuah tuturan dapat dilihat dengan menerapkan teori perolehan
praanggapan (pemahaman bersama) sehingga makna komunikasi yang
sebenarnya dari penutur dapat dimengerti oleh petutur.
Dari berbagai penelitian tersebut, secara umum dapat dipahami
bahwa terdapat persamaan dan perbedaan. Hal ini dapat dilihat pada
aspek-aspek pokok permasalahannya. Hasil-hasil penelitian tersebut
memiliki persamaan dengan penelitian ini terutama pada pendeskripsian
jenis-jenis praanggapan melalui kajian pragmatik. Perbedaannya ialah
terletak pada objek material dan aspek kajian yang dititikberatkan.
Adapun, penelitian ini akan berusaha menguraikan penggunaan
praanggapan, bentuk kalimat dan maksud kalimat yang terdapat pada
pamflet pada tiap-tiap penerbit dalam menyampaikan pesannya.
B. Landasan Teori
1. Pragmatik
Para pakar pragmatik mendefinisikan istilah pragmatik ini secara
berbeda-beda. Yule (2014: 3) menyebutkan 4 definsi pragmatik, yaitu (1)
bidang yang mengkaji makna pembicara, (2) bidang yang mengkaji makna
menurut konteksnya; (3) bidang yang melebihi kajian tentang makna yang
diujarkan, mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan
oleh pembicara, dan (4) bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut
16
jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan
tertentu. Menurut Levinson (1983: 9), ilmu pragmatik didefinisikan sebagai
kajian dari hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari
penjelasan pengertian bahasa. Di sini, pengertian/pemahaman bahasa´
menunjuk kepada fakta bahwa untuk mengerti sesuatu ungkapan/ujaran
bahasa diperlukan juga pengetahuan di luar makna kata dan hubungan
tata bahasanya, yakni hubungannya dengan konteks pemakaiannya.
Pragmatik ialah kajian tentang kemampuan pemakai bahasa mengaitkan
kalimat-kalimat dengan konteks-konteks yang sesuai bagi kalimat- kalimat
itu (Nababan, 1987: 2). Leech (2011: 8) mengemukakan bahwa pragmatik
sebagai studi meneliti makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi
tutur (speech situations). Pragmatik meneliti mengenai makna tuturan
yang dikehendaki oleh penutur dengan menurut konteksnya. Konteks
dalam hal ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam
mendeskripsikan makna tuturan dalam rangka penggunaan bahasa dalam
komunikasi.
Menurut Levinson (dalam Tarigan, 1990: 33), pragmatik merupakan
telaah mengenai relasi antara bahasa dengan konteks yang merupakan
dasar bagi suatu catatan atau laporan pemahaman bahasa. Dengan kata
lain, pragmatik adalah telaah mengenai kemampuan pemakai bahasa
menghubungkan serta menyerasikan kalimat-kalimat dan konteks-konteks
secara tepat. Pendapat lain dikemukakan oleh Wijana (1996: 14) bahwa
pragmatik menganalisis tuturan, baik tuturan panjang, satu kata atau. Ia
17
juga mengatakan bahwa pragmatik sebagai cabang ilmu bahasa yang
mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana suatu
kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi.
Hal senada juga di ungkapkan oleh Gusnawaty (2011:16)
pragmatik berfokus utama pada dua kunci, yakni penggunaan bahasa dan
konteksnya; dan makna yang ditimbulkan akibat interaksi sosial yang
bergantung pada hubungan solidaritas atau jarak antara interlekutor.
Penerapan pragmatik dalam kehidupan sehari-hari dapat diketahui
dengan menganalisis bentuk-bentuk penggunaan Bahasa, baik secara
lisan maupun tulisan yang berwujud tuturan. Menurut Cruse (dalam
Cummings, 2007: 3), pragmatik dapat dianggap berurusan dengan aspek-
aspek informasi (dalam pengertian yang luas) yang disampaikan melalui
bahasa yang (a) tidak dikodekan oleh konvensi yang diterima
secaraumum dalam bentuk-bentuk linguistik yang digunakan, namun (b)
juga muncul secara alamiah dari dan tergantung pada makna-makna yang
dikodekan secara konvensional dengan konteks tempat penggunaan
bentuk-bentuk tersebut (penekanan ditambahkan). Lebih lanjut, Rohmadi
(2014: 54) menjelaskan bahwa kajian pragmatik tidak dapat terlepas dari
konteks tuturan. Konteks yang dimaksudkan di sini adalah siapa yang
berbicara, kepada siapa, di mana, dan dalam situasi apa.
Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pragmatik
merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji segala aspek makna
tuturan baik lisan maupun tulisan berdasarkan maksud penutur yang
18
dihubungkan dengan konteks bahasa dan konteks nonbahasa. Konteks ini
sangat memengaruhi makna satuan bahasa, mulai dari kata sampai pada
sebuah wacana.
2. Pengertian Praanggapan
Praanggapan (presuposisi) berasal dari kata to pre-suppose, yang
dalam bahasa Inggris berarti to suppose beforehand (menduga
sebelumnya), dalam arti sebelum pembicara atau penulis mengujarkan
sesuatu ia sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang kawan bicara atau
hal yang dibicarakan. Stalnaker (dalam Yule. 1996: 39) berpendapat
bahwa praanggapan adalah apa yang digunakan penutur sebagai dasar
bersama bagi para peserta percakapan. Selain definisi tersebut, beberapa
definisi lain tentang praanggapan diantaranya adalah Levinson (dalam
Nababan, 1987: 48) memberikan konsep praanggapan yang disejajarkan
maknanya dengan presupposition sebagai suatu macam anggapan atau
pengetahuan latar belakang yang membuat suatu tindakan, teori, atau
ungkapan mempunyai makna. Adapun, menurut Cummings (2007: 42)
praanggapan adalah asumsi-asumsi atau inferensi-inferensi yang tersirat
dalam ungkapan linguistik tertentu.
Menurut Frege (dalam Mulyana 2005: 14) semua pernyataan
memiliki praanggapan, yaitu rujukan atau referensi dasar. Rujukan inilah
yang menyebabkan suatu ungkapan wacana dapat diterima atau
dimengerti oleh pasangan bicara, yang pada gilirannya komunikasi
tersebut akan dapat berlangsung dengan lancar. “Rujukan“ inilah yang
19
dimaksud sebagai “praanggapan“, yaitu anggapan dasar atau
penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa yang
membuat bentuk bahasa menjadi bermakna bagi pendengar atau
pembaca. Praanggapan membantu pembicara menentukan bentuk-bentuk
bahasa (kalimat) untuk mengungkapkan makna atau pesan yang ingin
dimaksudkan. Jadi, semua pernyataan atau ungkapan kalimat, baik yang
bersifat positif maupun negatif, tetap mengandung anggapan dasar
sebagai isi dan substansi dari kalimat tersebut.
Givon (dalam Yule 1996: 29) berpendapat bahwa pengertian
praanggapan yang diperlukan dalam wacana adalah praanggapan
pragmatis, yaitu yang ditentukan batas-batasnya berdasarkan anggapan-
anggapan pembicara mengenai apa yang kemungkinan akan diterima
oleh pendengar tanpa tantangan. Menurut Andryanto (2014: 3)
Praanggapan merupakan sesuatu ujaran yang mengandung makna
kebenaran atau ketidakbenaran sesuai dengan tuturannya. Lebih lanjut
Baisu (2015: 133) berpendapat bahwa praanggapan adalah kesimpulan
atau asumsi awal penutur sebelum melakukan tuturan bahwa apa yang
akan disampaikan juga dipahami oleh mitra tutur.
Praanggapan memiliki ciri-ciri tertentu yang mudah dikenali. Ciri-ciri
tersebut adalah:
a. Tetap Benar Walaupun Dinegasikan
Ciri-ciri praanggapan yang mendasar adalah sifat kebenaran di
bawah penyangkalan (Yule, 2014: 45). Hal ini memiliki maksud bahwa
20
praanggapan suatu pernyataan akan tetap benar walaupun kalimat itu
dijadikan kalimat negatif atau dinegasikan. Sebagai contoh perhatikan
beberapa kalimat berikut ini.
1) Gitar Budi itu baru.2) Gitar Budi tidak baru.
Kalimat (2) bentuk negatif dari kalimat (1). Praanggapan kalimat (1)
adalah Budi memiliki gitar. Dalam kalimat (2) ternyata praanggapan itu
tidak berubah meski kalimat (2) mengandung penyangkalan, yaitu
dengan adanya kata negasi tidak dari kalimat (1) yaitu memiliki
praanggapan yang sama bahwa Budi memiliki gitar.
Wijana (dalam Nadar, 2009: 64) menyatakan bahwa sebuah
kalimat dinyatakan mempraanggapankan kalimat yang lain jika
ketidakbenaran kalimat yang kedua (kalimat yang dipraanggapankan)
mengakibatkan kalimat pertama tidak dapat dikatakan benar atau
salah. Untuk memperjelas pernyataan tersebut perhatikan contoh
berikut ini.
3) Istri pejabat itu cantik sekali.4) Pejabat itu mempunyai istri.
Kalimat (4) merupakan praanggapan dari kalimat (3). Kalimat
tersebut dapat dinyatakan benar atau salahnya bila pejabat tersebut
mempunyai istri. Namun, bila berkebalikan dengan kenyataan yang ada
(pejabat tersebut tidak mempunyai istri), kalimat tersebut tidak dapat
ditentukan kebenarannya. Hal ini berarti bahwa praanggapan yang
21
dihasilkan oleh penggunaan unsur leksikal tetap sama walaupun
kalimat yang berisi unsur leksikal tersebut ditiadakan.
b. Dapat Dibatalkan
Seperti halnya implikatur percakapan, praanggapan juga dapat
dibatalkan atau dihapus. Praanggapan dapat dihapus jika tidak sesuai
dengan: asumsi yang tersirat, implikatur percakapan, dan konteks
kebahasaan. Selanjutnya, praanggapan dapat ditunda karena adanya
argumen-argumen yang terkurangi oleh kemungkinan-kemungkinan
yang ada dalam wacana. Perhatikan contoh berikut:
5)“Saya tidak bisa datang pagi besok karena ada halangan”.
Tuturan tersebut diungkapkan seseorang kepada temannya. Teman
tersebut pasti akan mempunyai praanggapan mungkin dia akan
mengantar anaknya sekolah atau ada halangan lain. Akan tetapi jika
seseorang tersebut melanjutkan ucapannya “Saya ada rapat dinas
penting besok pagi”, maka praanggapan akan batal karena sudah
diberitahukan langsung oleh penuturnya sehingga lawan tutur tidak
memiliki praanggapan lagi terhadap pernyataan tersebut.
Setelah memahami pendapat dari beberapa ahli di atas, peneliti
dapat menyimpulkan bahwa praanggapan dimaknai secara berbeda dari
tiap-tiap ahli bahasa. Namun demikian, dapat dilihat bahwa para ahli
menampilkan beberapa kesamaan sudut pandang. Dari sekian pendapat
yang ada, peneliti cenderung pada pendapat yang dikemukakan oleh
22
Cummings (2007: 42) karena lebih sederhana dan mudah dipahami,
namun sudah menyeluruh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
praanggapan merupakan pengetahuan awal yang dimiliki oleh penutur
sebagai dasar melahirkan tuturan.
Setelah mengetahui pengertian praanggapan menurut beberapa
ahli seperti yang telah dikemukakan di atas, penulis berusaha
memaparkan jenis-jenis praanggapan. Menurut Nababan (1987: 60),
mula-mula pengkajian praanggapan dikerjakan oleh ahli-ahli falsafah
dengan pendekatan semantik. Belakangan ini, linguis dan ahli
antropologi/sosiologi dan psikologi mengkaji praanggapan ini dengan
pendekatan pragmatik.
Pendapat senada diungkapkan oleh Cummings (2007: 42) bahwa
memang ciri-ciri praanggapan itu sendirilah yang telah menyebabkan
pokok permasalahan ini diteliti baik dilihat dari perspektif semantik
maupun pragmatik. Selanjutnya, Marmaridou (dalam Cummings, 2007:
52) mengatakan bahwa perlakuan pragmatik didasarkan pada
ketidakcukupan semantik yang bergantung pada kebenaran untuk
menerangkan banyak fenomena praanggapan.
Beberapa pendapat di atas, tampak jelas bahwa tidak terdapat
perbedaan yang signifikan terhadap pendapat para ahli bahasa tersebut
tentang jenis-jenis praanggapan, hanya mungkin terdapat perbedaan
istilah saja. Penulis dapat mengambil simpulan bahwa jenis praanggapan
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu praanggapan yang ditinjau dari segi
23
semantik dan praanggapan yang ditinjau dari segi pragmatik. Perbedaan
ini disebabkan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Marmaridou
(dalam Cummings, 2007: 52) di atas. Pada awalnya, praanggapan dikaji
berdasarkan ilmu semantik, jadi hanya berkutat pada makna leksikal dan
gramatikal saja. Namun, praanggapan semantik kurang dapat
menjelaskan pada aspek tertentu sehingga muncul pendapat baru ahli
bahasa yaitu praanggapan pragmatik yang telah mengaitkan aspek
konteks bahasa di dalam ujaran atau kalimat tersebut.
3. Pemerolehan Praanggapan
Untuk menemukan makna suatu teks dalam pamflet tidak sama
dengan menemukan makna suatu teks bacaan. Oleh karena itu kita harus
mengetahui penanda dari tiap-tiap praanggapan tersebut. Adapun
penanda yang mendukung kemunculan praanggapan terdiri dari tiga
unsur penting yaitu pengetahuan bersama, partisipan, dan konteks situasi
(Yule: 1996). Ketiga hal tersebut saling berkaitan dan merupakan
pembatas dalam menganalisis data tuturan ini:
a. Pengetahuan Bersama
Dalam memahami suatu tuturan, secara otomatis terdapat
suatu aturan tidak tertulis yang mengharuskan petutur memiliki
pemahaman mengenai struktur pengetahuan yang telah dimiliki
sebelumnya. Fungsi struktural ini berguna untuk melihat pola dalam
tuturan sehingga pemahaman yanng didapat sesuai dengan yang
diinginkan penutur (Yule, 1996: 85).
24
Salah satu unsur yang mendukung munculnya praanggapan
adalah memahami tuturan dalam adegan. Pengetahuan bersama ini
juga digunakan sebagai struktur yang membangun interpretasi yang
tidak muncul dalam teks atau tuturan. Untuk menyampaikan pesan
yang sesuai dengan tujuan penutur, pengetahuan bersama menjadi
sangat penting terutama untuk menghindari kesalahpahaman dalam
berkomunikasi. Segala hal yang berhubungan dan yang terjadi
selama tuturan berlangsung, bisa diasumsikan sebagai pengetahuan
bersama (Yule, 1996: 86 – 88).
b. Partisipan (Penutur dan Petutur)
Konsep penutur dan lawan tutur ini juga mencakup penulis dan
pembaca bila tuturan bersangkutan dikomunikasikan dengan media
tulisan. Aspek-aspek yang berkaitan dengan penutur dan lawan tutur
ini adalah usia, latar belakang, sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat
keakraban, dan sebagainya. Penutur adalah orang yang bertutur,
sementara mitra tutur adalah orang yang menjadi sasaran atau
kawan penutur.
Peran penutur dan mitra tutur dilakukan secara silih berganti,
penutur pada tahap tutur berikutnya dapat menjadi mitra tutur, begitu
pula sebaliknya sehingga terwujud interaksi dalam komunikasi.
Konsep tersebut juga mencakup penulis dan pembaca apabila
tuturan tersebut dikomunikasikan dalam bentuk tulisan. Aspek-aspek
yang terkait dengan penutur dan mitra tutur tersebut antara lain
25
aspek usia, latar belakang sosial, jenis kelamin, tingkat pendidikan,
dan tingkat keakraban. Aspek-aspek tersebut mempengaruhi daya
tangkap mitra tutur, produksi tuturan serta pengungkapan maksud.
Penutur dan mitra tutur dapat saling memahami maksud tuturan
apabila keduanya mengetahui aspek-aspek tersebut.
c. Konteks situasi
Halliday dan Hasan (1994: 62) membagi konteks situasi
menjadi tiga; yaitu (1) sebagai medan wacana, (2) sebagai pelibat
wacana, dan (3) sebagai sarana wacana. Medan wacana menunjuk
pada sesuatu yang sedang terjadi pada sifat (keformalan) tindakan
sosial yang sedang berlangsung. Medan wacana menunjuk kepada
orang yang mengambil bagian dalam peristiwa tutur, sedangkan
sarana tutur menunjuk kepada bagian yang diperankan oleh bahasa
seperti, organisasi teks, kedudukan dan fungsi yang dimiliki, saluran
yang digunakan, serta model retorikanya.
Selanjutnya Levinson (1983: 22-23) menjelaskan bahwa untuk
mengetahui sebuah konteks, seseorang harus membedakan antara
situasi aktual sebuah tuturan dalam semua keseragaman ciri-ciri
tuturan mereka dan pemilihan ciri-ciri tuturan tersebut secara budaya
dan linguistik yang berhubungan dengan produksi dan penafsiran
tuturan. Konteks ialah situasi atau latar terjadinya suatu komunikasi
(Mulyana, 2005:21). Menurutnya, konteks dianggap sebagai sebab
terjadinya suatu dialog, sehingga sesuatu yang berkaitan dengan
26
maksud tuturan sangat bergantung pada konteks yang
melatarbelakangi peristiwa komunikasi.
Oleh karena itu, bahasa hanya memiliki makna jika berada
dalam suatu konteks situasi. Makna sebuah ujaran diinterpretasikan
melalui sebuah ujaran dengan memperhatikan konteks, sebab
konteks yang akan menentukan makna sebuah ujaran berdasarkan
situasi. Artinya, konteks situasi sangat berpengaruh dalam
berinteraksi.
4. Jenis-jenis Praanggapan
Penelitian ini menggunakan teori yang diajukan oleh Yule (2014:
46-51) dalam menjelaskan jenis-jenis praanggapan yang terkandung
dalam pamflet. Menurut Yule, ada enam jenis praanggapan, yaitu:
praanggapan eksistensial, praanggapan faktif, praanggapan leksikal,
praanggapan nonfaktif, praanggapan struktural, dan praanggapan
konterfaktual.
Sebelumnya peneliti perkenalkan jenis-jenis praanggapan menurut
Levinson (1983). Levinson menyatakan adanya beberapa jenis-jenis
praanggapan yang masing-masing memiliki penanda dalam tuturan.
Praanggapan tersebut merupakan sesuatu yang diasumsikan oleh
penutur dalam sebuah pernyataan tuturan dan setelahnya akan ada
keterikutan (entailment) yang memiliki makna dan diasumsikan dalam
sebuah tuturan. Praanggpan juga diperlukan layaknya dua proposisi atau
usulan dalam sebuah tuturan.
27
Levinson (1983: 56) memaparkan sepuluh jenis praanggapan, yaitu
praanggapan eksistensial (existential presupposition), praanggapan
faktual (factive presupposition), praanggapan leksikal (lexical
presuppostion), praanggapan struktural (structural presupposition),
praanggapan tidak faktual (nonfactive presupposition) dan praanggapan
pengandaian (counter factual presuppostion), praanggapan iteratif
(iterative presupposition), praanggapan implikatif (implicative
presupposition), dan praanggapan waktu/temporal (temporal
presupposition).
Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Yule
(2014: 46-51) perihal jenis-jenis praanggapan dan akan dibantu oleh
proses pemerolehan praanggapan, situasi dan konteksnya pula demi
memperoleh makna praanggapan yang sebenarnya.
a. Praanggapan Eksistensial
Praanggapan eksistensial adalah praanggapan yang
menunjukkan eksistensi/ keberadaan/ jati diri referen yang diungkapkan
dengan kata yang definit. Jelasnya praanggapan ini tidak hanya
diasumsikan keberadaannya dalam kalimat-kalimat yang menunjukkan
kepemilikan, tetapi lebih luas lagi keberadaan atau eksistensi dari
pernyataan dalam tuturan tersebut. Praanggapan eksistensial
menunjukkan bagaimana keberadaan atas suatu hal dapat
disampaikan lewat praanggapan.
28
Contoh
6) Mobil itu berjalan.
Praanggapan dalam tuturan tersebut menyatakan keberadaan,
yaitu “ada mobil”.
b. Praanggapan Faktif
Praanggapan ini muncul dari informasi yang ingin disampaikan
dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta atau berita yang
diyakini keberadaannya. Praanggapan faktif adalah praanggapan
dimana informasi yang dipraanggapkan mengikuti kata kerja dapat
dianggap sebagai suatu kenyataan. Kata-kata yang bisa menyatakan
fakta dalam tuturan ialah kata kerja yang dapat memberikan makna
pasti tuturan tersebut.
Contoh
7) Kami menyesal mengatakan kepadanya.
Praanggapan kalimat diatas adalah “kami mengatakan
kepadanya”. Pernyataan tersebut menjadi faktual karena telah
disebutkan dalam tuturan. Penggunaan kata mengatakan, mengetahui,
sadar, mau adalah kata-kata yang menyatakan sesuatu yang
dinyatakan sebagai sebuah fakta dari sebuah tuturan. Walaupun di
dalam tuturan tidak ada kata-kata tersebut, kefaktualan suatu tuturan
yang muncul dalam praanggapan bisa dilihat dari partisipan tutur,
konteks situasi, dan juga pengetahuan bersama.
29
c. Praanggapan Leksikal
Praanggapan leksikal dipahami sebagai bentuk praanggapan
yang menyatakan makna secara konvensional ditafsirkan dengan
praanggapan bahwa suatu makna lain (yang tidak dinyatakan)
dipahami. Praanggapan ini merupakan praanggapan yang didapat
melalui tuturan yang diinterpretasikan melalui penegasan dalam
tuturan. Berbeda dengan praanggapan faktif, tuturan yang merupakan
praanggapan leksikal dinyatakan dengan cara tersirat sehingga
penegasan atas praanggapan tuturan tersebut bisa didapat setelah
pernyataan dari tuturan tersebut. Terdapat beberapa satuan bahasa
yang digunakan sebagai penanda dalam praanggapan leksikal ini
seperti “memulai, menyelesaikan, melanjutkan, membawa,
meninggalkan, berhenti”.
Contoh
8) Mereka mulai mengeluh.
Praanggapan pada tuturan diatas adalah “Sebelumnya mereka
tidak mengeluh”. Praanggapan tersebut muncul dengan adanya
penggunaan kata ‘mulai’ bahwa sebelumnya tidak mengeluh namun
sekarang mengeluh.
d. Praanggapan Nonfaktif
Praanggapan nonfaktif adalah suatu praanggapan yang
diasumsikan tidak benar. Praanggapan ini masih memungkinkan
30
adanya pemahaman yang salah karena penggunaan kata-kata yang
tidak pasti atau ambigu.
Contoh
9) Andai aku seorang anggota DPR.
Dari tuturan diatas praanggapan yang muncul adalah “Aku bukan
anggota DPR”. Penggunaan ‘andai’ sebagai pengandaian bisa
memunculkan praanggapan non-faktif. Selain itu praanggapan yang
tidak faktual bisa diasumsikan melelui tuturan yang kebenarannya
masih diragukan dari fakta yang disampaikan.
e. Praanggapan Struktural
Praanggapan struktural mengacu pada sturktur kalimat-kalimat
tertentu telah dianalisis sebagai praanggapan secara tetap dan
konvensional bahwa bagian struktur itu sudah diasumsikan
kebenarannya. Hal ini tampak dalam kalimat tanya, secara
konvensional diinterpretasikan dengan kata tanya (kapan dan di mana)
sesudah diketahui sebagai masalah, pertanyaan alternatif (Alternative
Question), dan pertanyaan ya/tidak (Yes/No Question). Dengan kata
lain praanggapan ini dinyatakan dengan tuturan yang strukturnya jelas
dan langsung dipahami tanpa melihat kata-kata yang digunakan.
Contoh
10) Kemana Gayus bertamasya?
Tuturan di atas menunjukkan praanggapan yaitu “Gayus
bertamasya”. Praanggapan yang menyatakan ‘keberadaan’ sebagai
31
bahan pembicaraan yang dipahami oleh penutur melalui struktur
kalimat tanya yang menanyakan ‘kemana’.
f. Praanggapan konterfaktual
Praanggapan konterfaktual berarti bahwa yang dipraanggapkan
tidak hanya tidak benar, tetapi juga merupakan kebalikan (lawan) dari
benar atau bertolak belakang dengan kenyataan. Rahardi (2002: 42)
memberikan contoh yang berkaitan dengan praanggapan ini:
Tuturan yang berbunyi “kalau kamu sudah sampai Jakarta,
tolong aku diberi kabar. Jangan sampai lupa, aku tidak ada di rumah
karena bukan hari libur”. Tuturan itu tidak semata-mata dimaksudkan di
dalam tuturan itu melainkan ada sesuatu yang tersirat dari tuturan itu
yang harus dilakukannya, seperti misalnya mencari alamat kantor atau
nomor telepon si penutur. Praanggapan ini menghasilkan pemahaman
yang berkelebihan dari pernyataannya atau kontradiktif. Kondisi yang
menghasilkan praanggapan seperti ini biasanya dalam tuturannya
mengandung ‘if clause’ atau pengandaian. Hasil yang didapat menjadi
kontradiktif dari pernyataan sebelumnya.
Contoh
11) Kalau Angie mengaku, dia akan dipenjara.
Dari contoh di atas kita akan menemukan praanggapan yang
muncul adalah Angie tidak mengaku. Praanggapan tersebut muncul
dari kontradiksi kalimat dengan adanya penggunaan kata ‘kalau’.
32
Penggunaan kalau membuat praanggapan yang kontradiktif dari tuturan
yang disampaikan.
5. Bentuk Kalimat dan Maksud
Dalam memahami suatu bahasa yang akan dikaji menurut
penuturnya, tidak cukup hanya diklasifikasikan berdasarkan jenis
praanggapannya saja, tetapi juga harus bisa dipahami berdasarkan
bentuk kalimat yang digunakan dalam pamflet tersebut. Tujuannya agar
diketahui maksud tuturan tersebut.
Selain menjelaskan bentuk kalimat yang digunakan, penelitian ini
juga memaparkan maksud yang terkandung dalam pamflet sosialisasi
pelestarian lingkungan di Kabupaten Wakatobi. Adapun pengertian
maksud ialah: (1) sesuatu yang dikehendaki, atau dapat diartikan pula
sebagai tujuan; (2) arti; makna dari suatu perbuatan, perkataan, peristiwa
(Poerwadarminta, 2011: 865). Sehubungan dengan pragmatik, salah satu
hal yang dikaji ialah maksud penutur (speaker meaning) atau (speaker
sense), sehingga maksud yang diutarakan oleh penutur terikat dengan
situsasi tutur (Wijana, 1996: 3). Wijana (1996: 10-11) juga menyatakan
bahwa terdapat sejumlah aspek yang senantiasa harus dipertimbangkan
dalam studi pragmatik yang dikemukakan oleh Leech (1993: 20), di
antaranya ialah aspek mengenai tujuan tuturan.
Bentuk-bentuk kalimat yang diutarakan oleh penutur
dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan tertentu, sehingga di dalam
pragmatik, berbicara merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan
33
(goal oriented activities). Adapun bentuk-bentuk kalimat yang bermacam-
macam dapat digunakan untuk menyatakan maksud yang sama, atau
bahkan sebaliknya. Oleh karena itu, mitra tutur harus mampu memahami
maksud yang disampaikan penutur guna mencapai tujuan tersebut.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksud adalah apa yang
dikehendaki penutur. Maksud tersebut dapat tersampaikan jika antara
penutur dan mitra tutur memiliki pemahaman dan pengetahuan yang
sama yang melatarbelakangi sebuah tuturan serta konteks situasi yang
terjadi dalam tuturan, sehingga apabila tidak terjadi kesinambungan di
dalamnya, maka maksud dari tuturan tersebut tidak akan tersampaikan
sebagaimana mestinya (Wijana, 2011: 15-16).
Kalimat adalah satuan gramatikal yang dibatasi oleh adanya jeda
panjang yang disertai nada akhir turun dan naik. Dalam wujud lisan
kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lemah, disertai jeda,
dan diakhiri intonasi naik dan turun. Sedangkan dalam wujud tulisan
kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik
(.), tanya (?), atau seru (!). Ramlan (2005: 23) membagi kalimat
berdasarkan bentuk sintaksisnya menjadi empat jenis yaitu: kalimat
deklaratif, kalimat interogatif, kalimat imperatif, dan kalimat ekslamatif.
a. Kalimat Deklaratif
Kalimat deklaratif (berita) adalah kalimat yang isinya
memberitahukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Hal
tersebut sejalan dengan pendapat Cook (1971: 38) kalimat deklaratif
34
adalah kalimat yang dibentuk untuk menyiarkan informasi tanpa
mengharapkan respon tertentu. Selanjutnya Ramlan (2005: 27) kalimat
berita adalah kalimat yang fungsinya untuk memberitahukan sesuatu
kepada orang lain hingga tanggapan yang diharapkan hanyalah berupa
perhatian seperti tercermin pada pandangan mata yang menunjukan
adanya perhatian. Adapun ciri-ciri kalimat berita yaitu:
a) isinya memberitahukan tentang sesuatu;
b) intonasinya netral dengan nada suara berakhir turun;
c) tanggapan pembaca atau pendengar tidak ada (zero); dan
d) dalam tulisan, penulisan kalimat berita diawali dengan huruf kapital
dan diakhiri dengan tanda titik (.).
Contoh
12) Putri memiliki lima ekor kucing.13) Ada minuman segar di dalam kulkas.14) Suaramu bagus sekali.
Contoh (12) merupakan kalimat deklaratif dengan maksud
pengutaraannya untuk memberitakan. Kalimat tersebut dituturkan untuk
memberitakan bahwa penutur memiliki lima ekor kucing. Berbeda pada
contoh (13), jika diucapkan kepada seorang teman yang membutuhkan
minuman yang segar, maka tuturan tersebut merupakan tuturan
dengan kalimat deklaratif yang maksud pengutaraannya adalah
memerintah petutur. Tuturan tersebut dimaksudkan untuk memerintah
petutur agar mengambil minuman yang ada di dalam kulkas, sehingga
kalimat tersebut digunakan oleh penutur bukan hanya untuk
35
memberitakan bahwa ada minuman yang segar di dalam kulkas
melainkan tuturan tersebut dimaksudkan untuk memerintah lawan tutur
mengambil minuman yang ada di dalam kulkas. Tuturan tersebut
dilakukan oleh penutur agar petutur tidak merasa bahwa dirinya
diperintah.
Contoh (14) merupakan kalimat deklaratif yang sesuai dengan
maksud tuturannya, tetapi kata-kata yang menyusunnya tidak memiliki
makna yang sama dengan maksud penuturnya. kalimat Tersebut
dituturkan ketika petutur sedang bernyanyi dihadapannya, namun
penutur menggunakan contoh tersebut yang maksud pengutaraannya
bukan berarti memberitakan bahwa suara yang dimiliki oleh mitra tutur
bagus melainkan suara yang dimiliki oleh mitra tutur tidak bagus dan
bermaksud agar memerintah petutur untuk lebih baik diam daripada
bernyanyi.
b. Kalimat Interogatif
Kalimat interogatif (tanya) adalah kalimat yang berisi pertanyaan
seseorang kepada orang lain dengan tujuan memperoleh jawaban dari
pihak yang ditanya. Adapun ciri-ciri kalimat tanya yaitu:
a) isinya menanyakan sesuatu;
b) intonasi tanya dengan nada suara naik pada akhir kalimat;
c) tanggapannya berupa jawaban;
d) dapat pula menggunakan partikel –kah yang berfungsi untuk
memperluas pertanyaan; dan
36
e) dalam tulisan, kalimat interogatif diawali dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda tanya (?).
Contoh
15) Dimanakah letak pulau Sumatera?16) Dimana piringnya?17) Kakak mau beli kue tidak?
Contoh (15) merupakan kalimat interogatif yang maksud
pengutaraannya hanya untuk bertanya. Kalimat tersebut digunakan
dengan maksud bertanya untuk menerima penjelasan dimana letak
pulau Sumatera tersebut. Berbeda dengan contoh (16), kalimat tersebut
merupakan kalimat interogatif yang tidak sesuai dengan maksud
pengutaraannya, tetapi makna kata-kata yang menyusunnya sesuai
dengan apa yang dimaksudkan penutur. Jika tuturan tersebut dilakukan
oleh seorang ibu kepada seorang anak, maka tuturan tersebut tidak
hanya semata-mata untuk menanyakan dimana letak piring tersebut,
sehingga pada contoh tersebut merupakan tuturan yang bukan hanya
bermaksud untuk bertanya saja melainkan memerintah mitra tutur untuk
mengambilkan piring yang dimaksud.
Contoh (17) merupakan kalimat interogatif. Kalimat tersebut
dituturkan oleh seorang penjual kue dan pada saat itu melihat
seseorang yang lewat dihadapannya, sehingga maksud tuturan
tersebut bukan hanya semata-mata untuk bertanya kepada mitra tutur
melainkan menawarkan kue yang telah disajikannya kepada mitra tutur.
37
c. Kalimat Imperatif
Kalimat imperatif (perintah) adalah kalimat yang isinya menyuruh
memberikan perintah kepada petutur untuk melakukan sesuatu yang
dikehendaki penutur. Ramlan (2005: 39) mengemukakan bahwa
berdasarkan fungsinya dalam hubungan situasi, kalimat perintah
mengharapkan tanggapan yang berupa tindakan dari orang yang diajak
berbicara. Adapun ciri-ciri kalimat perintah yaitu:
a) isinya perintah untuk melakukan sesuatu berupa permohonan,
ajakan, larangan, ejekan, atau harapan;
b) intonasi perintah dengan nada suara naik pada akhir kalimat;
c) tanggapannya berupa perbuatan;
d) dapat pula menggunakan partikel –lah;
e) kata kerja yang mendukung isi perintah biasanya merupakan kata
dasar; dan
f) dalam tulisan, kalimat imperatif diakhiri dengan tanda seru (!).
Contoh
18) Makanlah nak!19) Radionya keraskan lagi! Aku mau belajar besok ada
ulangan.20) Tolong letakkan bunga itu di halaman!
Contoh (18) merupakan kalimat imperatif. kalimat Tersebut
merupakan kalimat yang dituturkan oleh ibu kepada anak yang isi
tuturannya berupa perintah untuk makan. Contoh (19) merupakan
kalimat imperatif namun makna kalimat tidak sesuai dengan maksud
38
pengutaraannya. Kalimat tersebut jika diutarakan oleh seorang kakak
kepada seorang adiknya, maka tuturan tersebut merupakan kalimat
imperatif. Tuturan tersebut merupakan tuturan yang berisi permintaan
agar radio yang telah didengarkan oleh adiknya dimatikan atau
memerintah mitra tutur agar mematikan radio yang sedang
didengarkan. Contoh (20) merupakan kalimat imperatif yang maksud
pengutaraannya adalah permintaan penutur terhadap petutur agar
meletakkan bungan di halaman.
d. Kalimat Ekslamatif
Kalimat ekslamatif (seruan) adalah kalimat yang isinya
mengungkapkan kekaguman perasaan. Kalimat seruan disebut juga
kalimat interjeksi. Adapun ciri-ciri kalimat seruan yaitu:
a) mengungkapkan rasa kagum seperti pujian, terkejut, takut, menyapa,
atau menawarkan sesuatu;
b) urutan kalimatnya yaitu predikat + subjek;
c) biasanya terdapat partikel –nya pada predikat;
d) biasanya terdapat kata seru di depan predikat;
e) intonasi menunjukan keheranan dengan diakhiri nada naik; dan
f) dalam tulisan, Kalimat ekslamatif diakhiri dengan tanda seru (!).
Contoh
21) Pintarnya anak itu!22) Alangkah indahnya rambutmu nak!
39
Contoh (21) merupakan kalimat ekslamatif yang maksud
pengutaraannya mengungkapkan kekaguman. Kalimat tersebut
digunakan dengan maksud mengagumi jika benar-benar “anak itu
pintar”. Berbeda dengan contoh (22), kalimat tersebut merupakan
kalimat ekslamatif yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya,
tetapi makna kata-kata yang menyusunnya sesuai dengan apa yang
dimaksudkan penutur. Jika tuturan tersebut dilakukan oleh seorang ibu
kepada anak perempuannya dalam kondisi rambut acak-acakan, maka
tuturan merupakan tuturan yang bermaksud untuk memerintah anak
agar merapikan rambutnya.
6. Pengertian Pamflet
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2011:
1006) disebutkan bahwa pamflet adalah surat selebaran. Pamflet diartikan
sebagai tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak disertai
gambar, tanpa penyampulan maupun penjilidan, yang dicantumkan pada
selembar kertas di satu sisi atau kedua sisinya yang bertujuan untuk
mempengaruhi massa. Adapun menurut arti yang negatif (peyoratif),
pamflet adalah surat selebaran untuk menyerang seseorang atau mitra
tutur dengan cara membusuk-busukkan atau menghinanya. Pamflet juga
telah menjadi alat penting bagi protes politik dan kampanye.
Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau
tidak, tanpa penyampulan maupun penjilidan, yang dicantumkan pada
selembar kertas di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong
40
setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya, sehingga terlihat lebih
kecil (dapat juga disebut selebaran). Pamflet dapat pula terdiri dari
beberapa lembar kertas yang dilipat atau disatukan secara sederhana
sehingga menjadi sebuah buku kecil. Untuk dapat dikategorikan sebagai
sebuah pamflet, UNESCO mendefinisikannya sebagai keperluan publikasi
yang bisa terdiri dari 5 sampai 48 halaman tanpa sampul, bila lebih dari itu
disebut buku. Disebabkan oleh biayanya yang murah dan kemudahan
produksi serta distribusi, pamflet sering digunakan untuk mempopulerkan
ide-ide politik dan agama, atau untuk menyebarkan berita dan promosi /
iklan.
Pamflet adalah sebuah tulisan yang berisi tentang suatu informasi
yang terdiri dari tulisan termasuk gambar didalamnya yang umumnya
dibuat pada selebaran dan tidak dijilid atau dibukukan. Didalam pamflet
sendiri penggunaan gambar tidak wajib disertakan, gambar hanya
dijadikan tambahan untuk lebih menarik minat orang-orang dengan
pamflet yang diberikan. Pamflet umumnya digunakan sebagai media
promosi bagi beberapa perusahaan untuk memperkenalkan produknya ke
masyarakat. Banyak yang menggunakannya sebagai sarana promosi
karena selain menghemat pengeluaran juga mudah dibuat, hanya
memerlukan keterampilan berbahasa yang baik serta menarik. Tujuan dari
pamflet sendiri berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya,
tergantung pamflet jenis apa yang dibuat. Misalnya Pamflet tentang
promosi, maka memiliki tujuan untuk memberikan informasi
41
mengenaiproduk, berbeda dengan pamflet tentang agama, biasanya berisi
tentang ilmu-ilmu agama.
Pamflet memiliki beberapa ciri sebagai berikut:
a. menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas;
b. bersifat persuasif, artinya berisi ajakan untuk membeli produk atau
mentaati sesuatu;
c. ditulis dengan jelas supaya mudah dibaca; dan
d. hal-hal yang disampaikan biasanya mengenai hal-hal baru atau
terupdate.
Berikut ini adalah jenis-jenis pamflet yang terdapat di sekitar kita.
a. Pamflet Politik, berisi mengenai hal-hal yang berbau politik seperti
ajakan untuk memilih calon-calon pemimpin dan lainnya.
b. Pamflet Pendidikan, berisi tentang informasi-informasi yang
berhubungan dengan dunia pendidikan seperti contohnya acara
seminar, lomba-lomba akademik dan lainnya.
c. Pamflet Niaga, berisi mengenai informasi mengenai produk-produk,
disertai dengan kalimat ajakan untuk membeli produk tersebut.
d. Pamflet kegiatan, berisi tentang berbagai acara atau kegiatan seperti
misalnya seminar, pentas seni dan lainnya.
C. Kerangka Pikir
Penelitian ini merupakan penelitian pragmatik yang menelaah salah
satu unsur pragmatik, yaitu praanggapan yang terdapat pada pamflet
sosialisasi pelestarian lingkungan di Kabupaten Wakatobi. Selanjutnya
42
diklasifikasi berdasarkan jenis-jenis praanggapannya. Jenis praanggapan
tersebut meliputi praanggapan eksistensial, praanggapan faktif,
praanggapan leksikal, praanggapan nonfaktif, praanggapan struktural, dan
praanggapan konterfaktual.
Dalam memahami suatu bahasa yang dikaji menurut penuturnya,
tidak cukup hanya diklasifikasikan berdasarkan jenis praanggapannya
saja, tetapi juga harus bisa dipahami berdasarkan bentuk kalimat yang
digunakan dalam pamflet tersebut. Tujuannya agar diketahui latar
belakang terjadinya tuturan tersebut. Adapun jenis-jenis kalimat tersebut
yaitu: kalimat deklaratif, kalimat imperatif, kalimat interogatif, dan kalimat
ekslamatif. Penelitian selanjutnya mengarah pada pengungkapan maksud
yang terkandung dalam pamflet sosialisasi pelestarian lingkungan di
Kabupaten Wakatobi yang meliputi memberitakan, mengajak, memerintah,
membujuk, menanyakan, dan mengapresiasi.
Pada tahap akhir peneliti menganalisis penggunaan praanggapan,
bentuk kalimat, dan maksud kalimat dalam pamflet pada tiap-tiap penerbit
pamflet sosialisasi pelestarian lingkungan di Kabupaten Wakatobi. Hal
demikian dapat digambarkan melalui bagan kerangka pikir berikut ini.
43
Bagan Kerangka Pikir
Maksud
1. Memberitakan2. Mengajak3. Memerintah4. Membujuk5. Menanyakan6. Mengapresiasi
Jenis Praanggapan
1. Eksistensial2. Faktif3. Leksikal4. Nonfaktif5. Struktural6. konterfaktual
Bentuk Kalimat
1. Deklaratif2. Interogatif3. Imperatif4. Ekslamatif
Praanggapan dalam PamfletSosialisasi Pelestarian
Lingkungan di KabupatenWakatobi
Teks dalam Pamflet Sosialisasi PelestarianLingkungan di Kabupaten Wakatobi
44
D. Defenisi Operasional
Untuk menghindari perbedaan penafisran antara penulis dengan
pembaca, maka peneliti perlu mengemukakan definisi operasional berikut
ini.
1. Praanggapan adalah kesimpulan atau asumsi awal penutur sebelum
melakukan tuturan bahwa apa yang akan disampaikan juga dipahami
oleh petutur.
2. Kalimat adalah satuan gramatikal yang dibatasi oleh adanya jeda
panjang yang disertai nada akhir turun dan naik sedangkan dalam
wujud tulisan kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan
tanda baca titik (.), tanya (?), atau seru (!).
3. Maksud adalah sesuatu yang dikehendaki, atau dapat diartikan pula
sebagai tujuan.
4. Teks adalah satuan bahasa berupa bahasa tulis maupun berupa
bahasa lisan yang dihasilkan oleh interaksi atau komunikasi manusia.
5. Pamflet adalah media komunikasi yang bersifat visual (tulisan) yang
berisi tentang suatu informasi yang terdiri dari tulisan termasuk
gambar didalamnya yang umumnya dibuat pada selebaran dan tidak
dijilid atau dibukukan.
45
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Artinya dalam
penelitian ini peneliti mengamati dan melakukan analisis terhadap kalimat-
kalimat dalam Pamflet Sosialisasi Pelestarian Lingkungan di Kabupaten
Wakatobi melalui pendekatan pragmatik. Kemudian, mendeskripsikan
jenis praanggapan, bentuk kalimat dan maksud, dan penggunaan
praanggapan, bentuk kalimat dan maksud kalimat yang terdapat pada
pamflet pada tiap-tiap penerbit pamflet sosialisasi pelestarian lingkungan
di Kabupaten Wakatobi.
Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan jenis
praanggapan, menjelaskan bentuk kalimat dan maksud, dan menguraikan
penggunaan praanggapan, bentuk kalimat dan maksud kalimat yang
terdapat pada pamflet pada tiap-tiap penerbit pamflet sosialisasi
pelestarian lingkungan di Kabupaten Wakatobi.
B. Sumber Data dan Jenis Data
Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah Pamflet
Sosialisasi Pelestarian Lingkungan di Kabupaten Wakatobi sedangkan
jenis data penelitian ini adalah data tulisan, berupa kalimat-kalimat dalam
pamflet yang mengandung praanggapan.
46
C. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitan yaitu wilayah Pulau Wangi-wangi dan sekitarnya,
yang meliputi semua ruang publik tempat terdapat pamflet sosialisasi
pelestarian lingkungan, seperti: Pantai Marina, Pasar Pagi Wanci, Pasar
Sentral Mandati, Pelabuhan Nelayan Bajo, dan pos-pos pusat informasi.
Peneliti menetap di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang
diperlukan selama tiga minggu pada bulan agustus 2017.
D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Sebelum melakukan penelitian, penulis memilih dan menentukan
metode dan teknik yang tepat dan mungkin dilaksanakan guna mencapai
tujuan penelitian, sehingga metode juga harus disesuaikan dengan teori
yang digunakan. Teknik dapat diartikan sebagai suatu cara yang kita
gunakan untuk memperoleh data.
Penulis melakukan pengamatan dan menyimak penggunaan
bahasa yang terdapat dalam pamflet-pamflet sosialisasi pelestarian
lingkungan di Kabupaten Wakatobi. Adapun metode simak dilakukan
dengan menyimak gambar-gambar atau foto-foto pamflet yang diperoleh
dari beberapa sumber yang berbeda, yaitu: pertama, berupa pamflet yang
dipajang di berbagai tempat utamanya ruang publik di Pulau Wangi-wangi,
Kabupaten Wakatobi. Kedua, media elektronik berupa internet dan media
sosial.
Metode tersebut, teknik yang dapat digunakan untuk melengkapi
metode simak tersebut antara lain.
47
1. Teknik Rekam
Teknik rekam yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu
perekaman visual dengan cara memotret pamflet-pamflet sosialisasi
pelestarian lingkungan di Kabupaten Wakatobi. Perekaman dilakukan
dengan bantuan alat perekam, yakni berupa smart phone.
2. Teknik Catat
Data-data yang telah dikumpulkan melalui teknik rekam
selanjutnya dilakukan pencatatan pada kartu data.
E. Teknik Analisis Data
Menurut Mahsun (2012: 117), tahapan analisis data merupakan
tahapan yang sangat menentukan, karena kaidah yang mengatur
keberadaan objek penelitian harus sudah diperoleh. Metode yang
digunakan pada tahap ini ialah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu
penggambaran kenyataan yang ditemukan sebagaimana adanya. Tahap-
tahap analisis yang digunakan sebagai berikut:
1. mengidentifikasi kalimat-kalimat yang mengandung praanggapan;
2. mengklasifikasi data berdasarkan permasalahan yang ada, yakni
jenis-jenis presuposisi dan bentuk kalimatnya;
3. menganalisis data dengan pendeskripsian secara mendetail
permasalahan yang tedapat dalam data yang telah dikumpulkan
berdasarkan teori yang berkaitan dengan praanggapan sebagai dasar
pedoman analisis; dan
4. penyajian hasil analisis data. Salah satu tahap penyajian hasil analisis
48
data dilakukan secara informal, yakni mendeskripsikan hasil analisis
dengan menggunakan perumusan yang dituangkan dalam bentuk
tulisan dengan menggunakan kata-kata biasa.
49
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Secara umum penelitian ini berkaitan dengan aspek kebahasaan
yang terjadi di wilayah Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara.
Aspek kebahasaan tersebut yakni jenis praanggapan dan penggunaan
modus pada pamflet sosialisasi pelestarian lingkungan.
Penelitian ini mengungkapkan jenis praanggapan pada pamflet
sosialisasi pelestarian lingkungan yaitu: (1) praanggapan eksistensial, (2)
praanggapan faktif, (3) praanggapan leksikal, (4) praanggapan struktural,
dan (5) praanggapan konterfaktual sedangkan praanggapan nonfaktif
tidak ditemukan. Selain itu penelitian juga mengungkapkan penggunaan
bentuk kalimat pada pamflet sosialisasi pelestarian lingkungan yaitu: (1)
kalimat deklaratif, (2) kalimat imperatif, (3) kalimat interogatif, dan (4)
kalimat ekslamatif sedangkan maksud pengutaraannya untuk memerintah
masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan. Untuk lebih
jelasnya akan diuraikan pada pembahasan berikut.
A. Praanggapan dan Bentuk Kalimat pada Pamflet Sosialisasi
Pelestarian Lingkungan di Kabupaten Wakatobi
Pada dasarnya semua pernyataan memiliki praanggapan, yaitu
rujukan atau referensi dasar. Rujukan inilah yang menyebabkan suatu
pernyataan dapat diterima atau dimengerti oleh pasangan bicara, yang
pada gilirannya komunikasi tersebut akan dapat berlangsung dengan
50
lancar. “Rujukan“ inilah yang dimaksud sebagai “praanggapan“, yaitu
anggapan dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi
berbahasa yang membuat bentuk bahasa menjadi bermakna bagi
pendengar atau pembaca. Praanggapan membantu pembicara
menentukan bentuk-bentuk bahasa (kalimat) untuk mengungkapkan
makna atau pesan yang ingin dimaksudkan. Jadi, semua pernyataan atau
ungkapan kalimat, baik yang bersifat positif maupun negatif, tetap
mengandung anggapan dasar sebagai isi dan substansi dari kalimat
tersebut. Begitupun dengan kalimat-kalimat yang terdapat pada pamflet
sosialisasi pelestarian lingkungan di Kabupaten Wakatobi ditemukan lima
jenis praanggapan.
1. Praanggapan Eksistensial
Praanggapan eksistensial adalah praanggapan yang
menunjukkan eksistensi/keberadaan/jati diri referen yang
diungkapkan dengan kata yang definit. Penggunaan praanggapan
eksistensial dapat dilihat pada contoh berikut ini.
Contoh 1
(a) Habis senam pungut sampah.(b) Keren...!!!
Lokasi : Pantai Marina
Partisipan : LSM Kamelia, dan masyrakat pengunjung
Pantai MarinaWaktu : 2017Konteks : pamflet dipegang oleh anak sekolah dasar
(SD) pada saat senam pagi.
51
Contoh (1) mencirikan praanggapan eksistensial. Keberadaan
praanggapan eksistensial tidak hanya diasumsikan pada kalimat-
kalimat, akan tetapi dapat lebih diperluas dengan mengidentifikasi
keberadaan sesuatu dalam sebuah teks. Penanda praanggapan
eksistensial pada contoh di atas merujuk pada satuan bahasa
sampah, yang mengindikasikan bahwa ada sampah di pantai marina.
Jadi praanggapannya, yaitu ada sampah atau sampah berserakan di
Pantai Marina.
Bentuk kalimat yang digunakan pada butir (a) berbentuk
kalimat deklaratif. Hal ini tampak pada dua hal, yang pertama; isi
kalimat tersebut yang meberitakan suatu tindakan, kedua; fungsinya
untuk memberitahukan kepada orang lain hingga tanggapan yang
diharapkan hanyalah berupa perhatian. LSM Kamelia sebagai
penerbit pamflet menggunakan jasa anak-anak untuk memajang
pamflet dengan tujuan memberikan efek ketersinggungan kepada
pengunjung Pantai Marina. Asumsinya bahwa anak-anak saja sudah
turut berpartisipasi menjaga kebersihan, apalagi orang dewasa. Jika
merujuk pada konteks yang melingkupi contoh (1), maka kalimat
tersebut dimaksudkan untuk memerintah petutur agar turut serta
memelihara kebersihan Pantai Marina. Artinya bahwa LSM
menyampaikan pesan melalui pamflet secara tak langsung. Hal ini
dilakukan oleh penutur agar petutur tidak merasa bahwa dirinya
diperintah.
52
Adapun penggunaan bentuk kalimat pada butir (b) berbentuk
kalimat ekslamatif. Hal ini tampak pada penggunaan satuan bahasa
keren dan tanda seru (!). Satuan bahasa keren bermakna tampak
gagah dan tangkas. Adapun penggunaan satuan bahasa keren...!!!
pada contoh (2) bermakna pujian terhadap pengunjung Pantai
Marina jika melakukan hal sebagaimana pada butir (a). LSM Kamelia
sebagai penerbit pamflet menggunakan jasa anak-anak untuk
memajang pamflet dengan tujuan memberikan efek ketersinggungan
kepada pengunjung Pantai Marina. Asumsinya bahwa anak-anak
saja sudah turut berpartisipasi menjaga kebersihan, apalagi orang
dewasa. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, maka contoh (2)
butir (b) digunakan oleh penutur untuk memerintah petutur
(pengunjung Pantai Marina) agar ikut serta dalam memelihara
kebersihan Pantai Marina. Artinya bahwa kalimat ekslamatif
digunakan penutur untuk menyampaikan pesan melalui pamflet
secara tak langsung. Hal ini dilakukan oleh penutur agar mitra tutur
tidak merasa bahwa dirinya diperintah.
Contoh 2
(a)Wakatobi bersih tanpa sampah.(b)Stop buang sampah ke laut.
Lokasi : Pantai MarinaPartisipan : LSM Kamelia, dan masyrakat pengunjung
Pantai MarinaWaktu : 2017Konteks : pamflet dipegang oleh anak sekolah dasar
(SD) pada saat senam pagi
53
Praanggapan eksistensial pada contoh (2) terdapat pada butir
(a). Keberadaan praanggapan tersebut tidak hanya diasumsikan
pada penanda satuan bahasa, akan tetapi dapat lebih diperluas
dengan mengidentifikasi keberadaan sesuatu hal melalui konteks
situasi dan pemahaman bersama. Sebagaimana diketahui bahwa
suatu kegiatan senam pagi yang melibatkan banyak orang selalu
menyisakan sampah. Sehingga dapat dipahami praanggapannya
yakni ada sampah. pernyataan tersebut bermakna jika ingin
mewujudkan wakatobi bersih, maka harus meniadakan sampah.
Bentuk kalimat yang digunakan pada butir (a) berbentuk
kalimat deklaratif. Hal ini tampak pada konten kalimat tersebut
berupa pernyataan. Pamflet pada contoh (2) diterbitkan oleh LSM
Kamelia, namun dalam upaya menyosialisasikan pelestarian
lingkungan melibatkan anak-anak dengan maksud pesan yang
disampaikan tercapai. Peran anak-anak dalam konteks ini sangatlah
penting sebab dapat menghasilkan beberapa manfaat. Manfaat
tersebut diantaranya: pendidikan anak sejak dini, memicu perhatian,
dan pengaruh psikologis kepada orang dewasa. Jadi, merujuk pada
konteks yang melingkupi contoh (3), maka kalimat tersebut
dimaksudkan untuk memerintah petutur agar turut serta memelihara
kebersihan Pantai Marina. Artinya bahwa LSM menyampaikan pesan
melalui pamflet secara tak langsung. Hal ini dilakukan oleh penutur
agar petutur tidak merasa bahwa dirinya diperintah.
54
Contoh 3
Sampahmu milikmu!!
Lokasi : Pantai MarinaPartisipan : LSM Kamelia, dan masyrakat pengunjung
Pantai MarinaWaktu : 2017Konteks : pamflet dipegang oleh anak perempuan dan
bapaknya pada saat senam pagi.
Contoh (3) memenuhi ciri praanggapan eksistensial yaitu
menunjukan kepemilikan dan keberadaan dari pernyataan tersebut.
Ciri yang menunjukan kepemilikan ditandai oleh satuan bahasa
sampahmu. Jika ditinjau dari aspek makna maka satuan bahasa
sampahmu bermakna kamu memiliki sampah, sehingga kehadiran
satuan bahasa milikmu hanya sebagai penegasan. Selanjutnya, ciri
yang menunjukan keberadaan yaitu pada satuan lingual sampahmu
yang dihubungkan dengan konteks. Konteks yang dimaksud adalah
situasi senam pagi pada biasanya menyisakan banyak sampah.
Berdasarkan penjelasan tersebut bisa diketahui praanggapannya
yakni ada sampah atau banyak sampah atau sapah berserakan.
Sehingga pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sampah
merupakan tanggungjawab dari manusia itu sendiri untuk
membersihkannya.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (3) berbentuk
kalimat imperatif. Hal ini ditandai dengan penggunaan tanda seru (!).
Pamflet contoh (3) sampahmu milikmu!! diterbitkan oleh LSM
Kamelia. Lembaga tersebut melibatkan pihak lain (anak perempuan
55
dan bapaknya) dalam upaya menyosialisasikan kebersihan
lingkungan. Peran anak-anak sangat penting sebab dapat
menghasilkan beberapa manfaat. Manfaat tersebut diantaranya:
pendidikan anak sejak dini, memicu perhatian, dan pengaruh
psikologis kepada orang dewasa. Berkaitan dengan penjelasan
tersebut, maka contoh (5) digunakan oleh penutur bukan hanya
untuk meperingatkan kepemilikan sampah melainkan tuturan
tersebut dimaksudkan untuk memerintah petutur (pengunjung Pantai
Marina) untuk menjaga kebersihan. Artinya bahwa kalimat imperatif
digunakan penutur untuk menyampaikan pesan melalui pamflet
secara langsung.
Contoh 4
Nelayan yang gemar membom dan membius ikan adalahmusuh alam.
Lokasi : Pantai MarinaPartisipan : LSM Kamelia, dan masyrakat pengunjung
Pantai MarinaWaktu : 2017Konteks : pamflet dipegang oleh seorang pria dewasa
pada saat senam pagi
Contoh (4) mencirikan praanggapan eksistensial, walaupun
tidak terdapat kalimat yang menunjukan kepemilikan. Praanggapan
eksistensial dapat dipahami lebih luas lagi keberadaan sesuatu dari
pernyataan pada kalimat tersebut. Keberadaan yang dimaksud
adalah nelayan yang gemar mengebom dan membius ikan. Pada
lanjutan kalimatnya merupakan dakwaan terhadap nelayan tersebut
56
sebagai musuh alam. Dari penjelasan diatas dapat dipahami
praanggapannya yaitu ada nelayan yang sering mengebom dan
membius ikan atau nelayan belum memiliki kesadaran pentingnya
melestarikan lingkungan. Sehingga pernyataan tersebut dapat
dimaknai bahwa nelayan yang merusak biota laut mesti diperangi,
dalam hal ini perlunya kesadaran dari masyarakat untuk saling
mengingatkan betapa pentingnya melestarikan lingkungan.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (4) berbentuk
kalimat deklaratif. Hal ini tampak pada konten kalimat tersebut
berupa pernyataan. Satuan bahasa nelayan yang gemar membom
dan membius ikan merupakan pihak yang dianggap memusuhi alam.
Satuan bahasa alam bermakna lingkungan kehidupan. Secara
spesifik makna alam pada contoh (4) adalah manusia yang peduli
terhadap kelestarian kekayaan laut. Sejalan dengan penjelasan
tersebut, maka maksud kalimat tersebut adalah memerintah
pengunjung pantai Marina agar melestarikan kekayaan laut. Artinya
bahwa LSM menyampaikan pesan melalui pamflet secara tak
langsung.
Contoh 5
(a) Tak kenal maka tak sayang.(b) Lihatlah lebih dalam.(c) Lestarikan kekayaan lautmu.
Lokasi : perkampungan BajoPartisipan : LSM, dan masyarakat BajoWaktu : 2017Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi di
57
pelabuhan nelayan. Pelabuhan selalu ramaididatangi oleh masyarakat bajo yangmenunggu kerabat mereka pulang darimelaut. Selain itu banyak juga kalanganpenjual ikan yang menunggu nelayan danhendak membeli hasil tangkapannya. Isipamflet disertai gambar ikan-ikan dan terumbukarang.
Contoh (5), ungkapan tak kenal maka tak sayang pada butir
(a) merupakan bagian pengantar yang mengarahkan petutur untuk
mengenali. Pada bagian pengantar ini belum jelas apa yang akan
dikenali hingga sampai pada butir (b) yaitu lihatlah lebih dalam.
Kalimat tersebut menunjukan penjelasan yang masih samar-samar,
namun dapat dipahami melalui gambar ikan-ikan dan terumbu
karang dalam pamflet. Selain itu pada butir (c) disebutkan lestarikan
kekayaan lautmu, mengindikasikan maksud dari kalimat-kalimat
sebelumnya yaitu keberadaan kekayaan laut.
Merujuk pada ciri praanggpan eksistensial, maka
keberadaan jadi diri referen terletak pada kalimat butir (a) tak kenal
maka tak sayang dan butir (b) lihatlah lebih dalam. Adapun makna
pernyataan tersebut adalah menyuruh menyadari keberadaan
kekayaan laut. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui
praanggapannya yaitu ada kekayaan laut atau kekayaan laut belum
mendapat perhatian.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (5) butir (b)
berbentuk kalimat imperatif. Penanda kalimat imperatif pada butir (b)
58
tampak pada penggunaan partikel –lah pada satuan bahasa lihatlah
yang bermakna perintah untuk melihat. Secara konvensional satuan
bahasa lihatlah bermakna perintah untuk menjaga tetap seperti
keadaannya semula. Senada dengan uraian tersebut dapat dipahami
bahwa penutur bermaksud memerintah petutur khususnya
masyarakat Bajo agar menjaga kelestarian kekayaan laut. Artinya
bahwa kalimat imperatif digunakan penutur untuk menyampaikan
pesan melalui pamflet secara langsung.
Contoh 6
(a) Jaga dan cintai terumbu karang.(b) Mereka ada agar kami ada.
Lokasi : perkampugan BajoPartisipan : LSM, dan masyarakat BajoWaktu : 2017Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi di pos
informasi wisata komplek pendidikan dekatpintu gerbang perkampungan bajo. Isi pamfletdisertai gambar ikan-ikan dan terumbukarang.
Kedua kalimat pada contoh (6) ini mencirikan satu jenis
praanggapan yang sama yakni praanggapan eksistensial. Sebagai
penanda praanggapan eksistensial pada butir (a) yaitu satuan
bahasa terumbu karang. Adapun penanda praanggapan eksistensial
pada butir (b) tampak pada penggunaan satuan bahasa mereka ada
yang menunjukan eksistensi sesuatu walaupun tidak disebutkan
secara definit. Penggunaan satuan bahasa mereka ada merujuk
pada satuan bahasa terumbu karang pada butir (a). Sehingga dapat
59
diketahui praanggapannya yaitu ada terumbu karang atau terumbu
karang sebagai rumah ikan-ikan. Berdasarkan penjelasan tersebut
dapat dimaknai bahwa melestarikan terumbu karang dengan
sepenuh hati berkonsekuensi pada tersedianya ikan.
Bentuk kalimat yang digunakan pada butir (a) berbentuk
kalimat imperatif. Hal ini tampak pada penggunaan satuan bahasa
jaga dan cintai. Satuan bahasa jaga bermakna mempertahankan
keselamatan, dan satuan bahasa cintai bermakna menyuruh untuk
menyayangi. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, maka contoh (6)
butir (a) digunakan oleh penutur untuk memerintah petutur
(pengunjung pasar) agar melestarikan terumbu karang. Artinya
bahwa kalimat imperatif digunakan penutur untuk menyampaikan
pesan melalui pamflet secara langsung.
Adapun penggunaan bentuk kalimat pada butir (b) berbentuk
kalimat deklaratif. Hal ini tampak pada konten kalimat berupa
pernyataan. Sebagai penandanya yaitu satuan bahasa mereka ada,
kemudian diikiuti oleh satuan bahasa agar kami ada. Satuan bahasa
mereka ada merujuk pada butir (a) yaitu terumbu karang sedangkan
kami ada merujuk pada gambar pamflet yaitu ikan. Merujuk pada
konteks yang melingkupi contoh (6), maka dapat dipahami bahwa
LSM (penutur) bermaksud memerintah masyarakat (petutur) agar
menjaga terumbu karang. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka
dapat dipahami bahwa penutur menggunakan kalimat deklaratif yang
60
dimaksudkan untuk memerintah petutur. Artinya bahwa penutur
menyampaikan pesan melalui pamflet secara tak langsung. Hal ini
dilakukan oleh penutur agar petutur tidak merasa bahwa dirinya
diperintah.
Contoh 7
Jaga terumbu karang untuk anak cucu kita.
Lokasi : Pasar Sore WanciPartisipan : Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan
Pengunjung pasarWaktu : 2017Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi dekat
penjualan ikan
Contoh (7) mencirikan praanggapan eksistensial, walaupun
tidak terdapat kalimat yang menunjukan kepemilikan. Praanggapan
eksistensial dapat dipahami lebih luas lagi keberadaan sesuatu dari
pernyataan pada kalimat tersebut. Hal ini ditandai dengan
penggunaan satuan bahasa jaga terumbu karang yang menunjukan
keberadaan terumbu karang. Dari penjelasan tersebut dapat
dipahami praanggapannya yaitu ada terumbu karang. Adapun
makna pernyataan tersebut adalah melestarikan terumbu karang
berkonsekuensi pada tersedianya kekayaan laut hingga masa
depan.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (7) berbentuk
kalimat imperatif. Hal ini tampak pada penggunaan satuan bahasa
jaga. Satuan bahasa jaga bermakna mempertahankan keselamatan.
Dengan demikian kalimat jaga terumbu karang untuk anak cucu kita
61
dapat dipahami bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan
sebagai penerbit pamflet berupaya memerintah pengunjung pasar
sore (penutur) agar memelihara terumbu karang demi kelanjutan
ekosistem perikanan sehingga dapat dinikmati hingga generasi
mendatang. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, maka contoh (7)
digunakan oleh penutur untuk memerintah petutur (pengunjung
pasar) agar memelihara terumbu karang. Artinya bahwa kalimat
imperatif digunakan penutur untuk menyampaikan pesan melalui
pamflet secara langsung.
Contoh 8
(a) Terimakasih atas partisipasinya dalam melestarikanterumbu karang.
(b) Terumbu karang sehat, ikan berlimpah, masyarakatsejahtera.
Lokasi : Pasar Pagi WanciPartisipan : Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Coremap II, dan pengunjung pasarWaktu : 2017Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi
Praanggapan eksistensial pada contoh (8) terdapat pada butir
(b). Sebagai penanda praanggapan eksistensial pada butir (b) yaitu
satuan bahasa terumbu karang. Satuan bahasa terumbu karang
disebutkan secara definit sebagai eksistensi jadi diri dengan hadirnya
satuan bahasa sehat, lalu diikuti penjelasan pada bagian kalimat
selanjutnya yakni ikan berlimpah, masyarakat sejahtera. Sehingga
dapat diketahui praanggapannya yaitu ada terumbu karang.
Berdasarkan pendeskripsian tersebut dapat dimaknai bahwa
62
penerbit pamflet melalui pamflet memberikan gambaran tentang
dampak baik ketika terumbu karang sehat. Dengan demikian bisa
lahir kesadaran masyarakat untuk melestarikan terumbu karang demi
kepentingan masyarakat itu sendiri.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (8) butir (b)
berbentuk kalimat deklaratif. Hal ini tampak pada konten kalimat
berupa pernyataan yang saling keterkaitan. Konten kalimat tersebut
memiliki hubungan konsekuensi logis satu dengan yang lain yaitu
satuan bahasa terumbu karang mengakibatkan ikan berlimpah, ikan
berlimpah mengakibatkan masyarakat sejahtera. Kalimat tersebut
memberikan pengetahuan pentingnya menjaga terumbu karang.
Berkenaan dengan penjelasan tersebut dan merujuk pada
konteks pamflet maka, contoh (8) butir (b) berbentuk kalimat
deklaratif yang dimaksudkan untuk memerintah (menyuruh)
masyarakat yang belum melakukan hal serupa agar tersentuh untuk
menjaga terumbu karang. Artinya bahwa penutur menyampaikan
pesan melalui pamflet secara tak langsung. Hal ini dilakukan oleh
penutur agar petutur tidak merasa bahwa dirinya diperintah.
Contoh 9
(a) Sayangi karang.(b) Jangan injak karang.
Lokasi : Pasar Pagi WanciPartisipan : Coremap II, dan pengunjung pasarWaktu : 2017Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi
63
Contoh (9) mencirikan praanggapan eksistensial. Hal ini
tampak pada butir (a) sayangi karang. Satuan bahasa sayangi
karang bermakna memerintah untuk menyayangi karang. Secara
definit keberadaan karang langsung disebutkan. Pada butir (b)
keberadaan karang semakin diperjelas yaitu jangan injak karang.
Dengan demikian dapat diketahui praanggapannya yaitu ada karang.
Berdasarkan pendeskripsian tersebut dapat dimaknai bahwa
penerbit pamflet melalui pamflet mengajak masyarakat agar
menyayangi karang dengan cara tidak merusak karang.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (9) butir (a) dan
butir (b), keduanya berbentuk kalimat imperatif. Satuan bahasa
sayangi karang pada butir (a) bermakna perintah untuk menjaga
karang sepenuh hati. Demikian halnya pada butir (b) jangan injak
karang merupakan bentuk kalimat imperatif. Hal ini tampak pada
penggunaan Satuan bahasa jangan yang bermakna kata yang
menyatakan larangan. Sejalan dengan uraian tersebut dan merujuk
pada konteks pamflet maka, contoh (9) dimaksudkan untuk
memerintah masyarakat agar tidak merusak karang. Artinya bahwa
kalimat imperatif digunakan penutur untuk menyampaikan pesan
melalui pamflet secara langsung.
Contoh 10
(a) Ala sagaa, heboka ako tey langento.(b) Ambil sebagian, simpan untuk hari esok
Lokasi : Pasar Sore, Wanci
64
Partisipan : Coremap II, WWF, RARE, dan pengunjungpasar
Waktu : 2017Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi.
Pamflet dilengkapi dengan gambar ikan-ikan.
Butir (a) merupakan bahasa Pulo yang berarti ambil
sebagian, simpan untuk hari esok sebagaimana pada butir (b). Pada
contoh tersebut mencirikan praanggapan eksistensial. Praanggapan
eksistensial dapat dipahami lebih luas lagi keberadaan sesuatu dari
pernyataan pada kalimat tersebut. Pernyataan ambil sebagian,
simpan untuk hari esok merupakan kalimat yang mengandung
perintah melakukan sesuatu terhadap suatu objek tertentu. Objek
tersebut dapat dipahami melalui gambar ikan-ikan pada pamflet.
Artinya bahwa keberadaan sesuatu merujuk pada ikan-ikan.
Sehingga praanggapannya adalah ada ikan yang sering diambil
dalam jumlah yang banyak atau perlunya mengambil ikan sesuai
kebutuhan. Perlu diketahui bahwa, nelayan setempat masih banyak
yang melakukan penangkapan ikan secara berlebihan maka kalimat
pada pamflet tersebut dapat diketahui praanggapannya yaitu masih
sering terjadi penangkapan ikan secara berlebihan. Jadi,
berdasarkan pendeskripsian tersebut dapat dimaknai bahwa
kegiatan penangkapan ikan mesti terukur sesuai kebutuhan demi
terjaminnya ketersediaan ikan.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (10) butir (a) dan
butir (b), keduanya berbentuk kalimat imperatif. Butir (a) merupakan
65
bahasa Pulo yang berarti ambil sebagian, simpan untuk hari esok
sebagaimana pada butir (b). Kalimat imperatif pada contoh tersebut
ditandai dengan penggunaan satuan bahasa ambil yang bermakna
pegang sesuatu lalu dibawa, dan satuan bahasa simpan yang
bermakna menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak.
Adapun satuan bahasa ambil sebagian merujuk pada ikan-ikan yang
terdapat pada gambar pamflet. Berdasarkan penjelasan tersebut dan
merujuk pada konteks pamflet maka, contoh (10) dimaksudkan
memerintah masyarakat agar menangkap ikan sesuai kebutuhan.
Artinya bahwa kalimat imperatif digunakan penutur untuk
menyampaikan pesan melalui pamflet secara langsung.
Contoh 11
(a) Sadarkah anda?(b) Betapa berharganya mereka jika sudah dikelola(c) Kenali potensi dan peluang investasi pulau-pulau kecil
indonesia
Lokasi : Pasar Sore, WanciPartisipan : Coremap II, WWF, RARE, dan pengunjung
pasarWaktu : 2017Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi dekat
penjualan ikan
Praanggapan eksistensial pada contoh (11) terdapat pada
butir (b) dan butir (c). Kalimat tanya sadarkah anda? pada butir (a)
merupakan bagian pengantar untuk menstimulus pikiran petutur
tentang sesuatu sebagaimana pada butir (b), namun pada butir (b)
belum tampak informasi yang jelas. Artinya bahwa satuan bahasa
mereka masih samar-samar. Hal ini menjadi jelas ketika pada butir
66
(c), yaitu satuan bahasa mereka merujuk pulau-pulau kecil.
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa contoh (11)
butir (b) dan butir (c) mencirikan praanggapan eksistensial. Perlu
diketahui bahwa walaupun tidak disebutkan secara definit, namun
kedua pernyaataan tersebut dapat diketahui praanggapanya yaitu
ada pulau-pulau kecil atau potensi pulau-pulau kecil atau pulau-pulau
kecil berharga.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (11) butir (b)
berbentuk kalimat ekslamatif. Penanda kalimat ekslamatif pada butir
(b) tampak pada penggunaan satuan bahasa betapa, urutan kalimat
yaitu berharganya (predikat) + mereka (subjek), dan partikel –nya.
Satuan bahasa betapa bermakna kata seru penanda rasa heran,
kagum, sedih, dan sebagainya. Berkenaan dengan penjelasan
tersebut dan merujuk pada konteks yang melingkupi butir (b), maka
kalimat ekslamatif pada butir (b) bermaksud membujuk pengunjung
pasar (petutur) agar tertarik mengelola potensi dan peluang investasi
pulau-pulau kecil. Artinya bahwa kalimat ekslamatif digunakan
penutur untuk menyampaikan pesan melalui pamflet secara tak
langsung.
Adapun penggunaan bentuk kalimat pada contoh (11) butir (c)
berbentuk kalimat imperatif. Hal ini tampak pada penggunaan satuan
bahasa kenali. Satuan bahasa kenal bermakna tahu dan teringat
kembali mendapatkan sufiks –i menjadi kenali sehingga secara
67
konvensional bermakna perintah atau ajakan untuk mengetahui atau
mengingat kembali. Berkaitan dengan penjelasan tersebut dan
merujuk pada konteks yang melingkupi butir (c), maka kalimat
tersebut digunakan oleh penutur untuk memerintah petutur
(pengunjung pasar) agar menyadari, memahami lalu menjeput
peluang investasi pulau-pulau kecil. Artinya bahwa kalimat imperatif
digunakan penutur untuk menyampaikan pesan melalui pamflet
secara langsung.
Contoh 12
(a) Tahukah kamu laut indonesia sangat kaya?(b) Ikan melimpah nelayan sejahtera.
Lokasi : Pasar sentral,MandatiPartisipan : Coremap II, WWF, RARE, dan pengunjung
pasarWaktu : 2017Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi dekat
terminal
Praanggapan eksistensial pada contoh (12) terdapat pada
butir (b). Sebagai penanda praanggapan eksistensial pada butir (b)
yaitu satuan bahasa ikan melimpah. Satuan bahasa ikan melimpah
disebutkan secara definit sebagai eksistensi jadi diri, lalu diikuti
penjelasan pada bagian kalimat selanjutnya yakni nelayan sejahtera.
Sehingga dapat diketahui praanggapannya yaitu ada ikan.
Berdasarkan pendeskripsian tersebut dan mempertimbangkan
konteks yang meliputinya, maka dapat dimaknai bahwa penerbit
pamflet mengajak masyarakat agar melestarikan lingkungan demi
68
menjaga ketersediaan ikan yang nantinya berkonsekuensi pada
kesejahteraan nelayan.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (12) butir (b)
berbentuk kalimat deklaratif. Hal ini tampak pada konten kalimat
berupa pernyataan yang saling keterkaitan. Konten kalimat tersebut
memiliki hubungan konsekuensi logis satu dengan yang lain yaitu
satuan bahasa ikan berlimpah mengakibatkan nelayan sejahtera.
Kalimat tersebut memberikan pengetahuan pentingnya menjaga
kelestarian ikan. Berkenaan dengan penjelasan tersebut dan
merujuk pada konteks pamflet maka, contoh (20) butir (b) berbentuk
kalimat deklaratif yang dimaksudkan memberitahu pengunjung pasar
agar menyadari pentingnya menjaga kelestarian ikan. Selain itu,
kalimat tersebut juga bermaksud menyuruh masyarakat khususnya
nelayan agar menjaga kelestarian ikan tentunya dengan cara tidak
merusak termbu karang demi mewujudkan kehidupan yang
sejahtera. Artinya bahwa penutur menyampaikan pesan melalui
pamflet secara tak langsung. Hal ini dilakukan oleh penutur agar
petutur tidak merasa bahwa dirinya diperintah.
Dari penjelasan tersebut dapat digambarkan penggunaan
bentuk kalimat dan maksud pada tiap-tiap praanggapan eksistensial.
Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut ini.
69
Tabel 4.1. Penggunaan bentuk kalimat pada praanggapan eksistensial
Contoh
Bentuk Kalimat
MaksudDek Imp Int Eks
(1.a) Habis senam pungut sampah. + memerintah
(2.a) Wakatobi bersih tanpa sampah. + memerintah
(3) Sampahmu milikmu!! + memerintah
(4) Nelayan yang gemar membom danmembius ikan adalah musuh alam.
+ memerintah
(5.a)Tak kenal maka tak sayang. + memerintah
(5.b) Lihatlah lebih dalam. + memerintah
(6.a) Jaga dan cintai terumbu karang. + memerintah
(6.b) Mereka ada agar kami ada. + Memerintah
(7) Jaga terumbu karang untuk anak cucukita.
+ Memerintah
(8.b) Terumbu karang sehat, ikanberlimpah, masyarakat sejahtera.
+ Memerintah
(9.a) Sayangi karang. + Memerintah
(9.b) Jangan injak karang. + Memerintah
(10.a) Ala sagaa, heboka ako tey langento. + Memerintah
(10.b) Ambil sebagian, simpan untuk hariesok
+ Memerintah
(11.b) Betapa berharganya mereka jikasudah dikelola
+ Membujuk
(11.c) Kenali potensi dan peluanginvestasi pulau-pulau kecil Indonesia
+ Memerintah
12(b) Ikan melimpah nelayan sejahtera. + Memerintah
Jumlah 6 10 - 1
Pada tabel (4.1.) tampak bahwa terdapat tujuh belas
praanggapan eksistensial. Paraanggapan tersebut dominan
direalisasikan dengan menggunakan kalimat imperatif. Adapun
maksud dari keseluruhan praanggapan tersebut yaitu: memerintah
dan membujuk.
70
2. Praanggapan Faktif
Praanggapan faktif adalah praanggapan dimana informasi
yang dipraanggapkan mengikuti kata kerja dapat dianggap sebagai
suatu kenyataan. Praanggapan ini muncul dari informasi yang ingin
disampaikan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta atau
berita yang diyakini kebenarannya. Kata-kata yang bisa menyatakan
fakta dalam tuturan ialah kata kerja yang dapat memberikan makna
pasti tuturan tersebut. Penggunaan praanggapan faktif dapat dilihat
pada contoh berikut ini.
Contoh 13
Selamatkan laut indonesia dari sampah karena laut masadepan bangsa.
Lokasi : Perkampungan BajoPartisipan : Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan
masyrakat BajoWaktu : 2017Konteks : hari peduli sampah nasional 2017
Contoh (13) mencirikan praanggapan faktif. Praanggapan ini
mengacu pada penanda satuan bahasa selamatkan. Penanda ini
bukanlah sebuah penanda umum yang dipaparkan sesuai dengan
teori pada bab sebelumnya. Praanggapan faktif ini dapat hadir dalam
sebuah pernyataan tanpa adanya penanda-penanda umum dengan
hadirnya penanda yang menunjukan kefaktualan, dukungan konteks
dan pemahaman bersama. Seperti halnya penggunaan satuan
bahasa selamatkan, secara konvensional dapat dimaknai sebagai
bentuk perintah yang berarti menyuruh membebaskan dari bahaya.
71
Selain itu, pernyataan tersebut disampaikan pada peringatan Hari
Peduli Sampah Nasional. Sampah merupakan persoalan yang belum
dapat ditanggulangi dengan baik di Wakatobi. Hal ini terbukti masih
banyak ditemukannya sampah di laut yang merupakan limbah
masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami
bahwa praanggapannya yakni laut indonesia khususnya wakatobi
sedang tercemari oleh sampah atau laut indonesia butuh perhatian
serius perihal penanganan sampah.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (13) berbentuk
kalimat imperatif. Hal ini tampak pada penggunaan satuan bahasa
selamatkan. Selamat bermakna terbebas dari bahaya. Adapun
penggunaan satuan lingual selamatkan secara konvensional
bermakna perintah atau ajakan untuk melakukan sesuatu sesuai
maksud penutur. Berdasarkan penjelasan tersebut dan merujuk pada
konteks yang melingkupi pamflet dapat dipahami bahwa contoh (13)
merupakan kalimat imperatif yang digunakan penutur dengan
maksud memerintah petutur agar menjaga kebersihan laut. Artinya
bahwa kalimat imperatif digunakan penutur untuk menyampaikan
pesan melalui pamflet secara langsung.
Contoh 14
(a) Save Turtle.(b) Lestarikan penyu dan jangan jadikan mereka buruan.
Lokasi : Pantai MarinaPartisipan : LSM Kamelia, dan masyrakat pengunjung
Pantai Marina
72
Waktu : 2017Konteks : pamflet dipegang oleh anak laki-laki dan
ibunya pada saat senam pagi.
Contoh (14) mencirikan praanggapan faktif. Praanggapan ini
mengacu pada penanda satuan bahasa save pada butir (a) dan
satuan bahasa lestarikan pada butir (b). Satuan bahasa save turtle
(bahasa inggris) pada butir (a) berarti selamatkan penyu. Penanda-
penanda ini bukanlah sebuah penanda umum yang dipaparkan
sesuai dengan teori di bab sebelumnya. Akan tetapi dapat dipahami
bahwa praanggapan faktif ini dapat hadir dalam sebuah pernyataan
tanpa adanya penanda-penanda umum dengan hadirnya penanda
yang menunjukan kefaktualan, dukungan konteks dan pemahaman
bersama. Seperti halnya penggunaan satuan bahasa save turtle dan
lestarikan secara konvensional dapat dimaknai sebagai bentuk
perintah yang berarti menyuruh membebaskan penyu dari bahaya.
Selain itu, di wilayah Wakatobi terdapat banyak pulau tempat
pemijahan penyu yang terancam akibat maraknya perburuan telur
penyu dan penyu. Hal ini terbukti masih banyak ditemukan kasus
pelanggaran perburuan penyu. Berdasarkan penjelasan tersebut
dapat dipahami bahwa praanggapannya yakni kelangsunagan
populasi penyu sedang terancam atau penyu dijadikan buruan.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (14) butir (a) dan
butir (b), keduanya berbentuk kalimat imperatif. Satuan bahasa save
turtle pada butir (a) berarti selamatkan penyu. Selamat bermakna
73
terbebas dari bahaya. Adapun penggunaan satuan lingual
selamatkan secara konvensional bermakna perintah atau ajakan
untuk melakukan sesuatu sesuai maksud penutur. Sama halnya
pada butir (b) berbentuk kalimat imperatif. Hal ini tampak pada
penggunaan satuan lingual lestarikan. Lestari bermakna tetap seperti
keadaannya semula. Adapun penggunaan satuan lingual lestarikan
bermakna perintah atau ajakan untuk menjaga tetap seperti
keadaannya semula.
LSM Kamelia sebagai penerbit pamflet melibatkan anak-anak
dalam upaya menyosialisasikan pelestarian penyu. Peran anak-anak
sangat penting sebab dapat menghasilkan beberapa manfaat.
Manfaat tersebut diantaranya: pendidikan anak sejak dini, memicu
perhatian, dan pengaruh psikologis kepada orang dewasa. Merujuk
pada konteks yang melingkupi contoh (14), maka kedua kalimat
tersebut dimaksudkan untuk memerintah petutur agar turut serta
melestarikan penyu. Artinya bahwa kalimat imperatif digunakan
penutur untuk menyampaikan pesan melalui pamflet secara
langsung.
Contoh 15
(a)Save me guys.(b)Ikan hiu adalah teman bukan untuk dimakan.
Lokasi : Pantai MarinaPartisipan : LSM Kamelia, dan masyrakat pengunjung
Pantai MarinaWaktu : 2017Konteks : pamflet dipegang oleh anak sekolah dasar
74
(SD) pada saat senam pagi.
praanggapan faktif pada contoh (15) terdapat pada butir (a).
Praanggapan ini mengacu pada penanda satuan bahasa save.
Satuan bahasa save me guys pada butir (a) berarti selamatkan saya
kawan. Satuan bahasa me merujuk pada ikan hiu pada butir (b).
Penanda ini bukanlah sebuah penanda umum yang dipaparkan
sesuai dengan teori di bab sebelumnya. Akan tetapi dapat dipahami
bahwa praanggapan faktif ini dapat hadir dalam sebuah pernyataan
tanpa adanya penanda-penanda umum dengan hadirnya penanda
yang menunjukan kefaktualan, dukungan konteks dan pemahaman
bersama. Seperti halnya penggunaan satuan bahasa save me guys,
secara konvensional bermakna perintah atau menyuruh
membebaskan ikan hiu dari bahaya.
Selain itu, di wilayah Wakatobi terdapat banyak ikan hiu yang
terancam akibat maraknya perburuan sirip ikan hiu. Sirip ikan hiu
merupakan salah satu komoditas yang terbilang mahal. Hal ini
terbukti masih banyak ditemukan transaksi jual beli komoditas
tersebut yang luput dari pantauan petugas. Berdasarkan penjelasan
tersebut dapat dipahami bahwa praanggapannya yakni
kelangsunagan populasi ikan hiu sedang terancam.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (15) butir (a)
berbentuk kalimat imperatif. Butir (a) save me guys yang berarti
selamatkan saya kawan. Selamat bermakna terbebas dari bahaya.
75
Adapun penggunaan satuan lingual selamatkan secara konvensional
bermakna perintah atau ajakan untuk melakukan sesuatu sesuai
maksud penutur. Satuan bahasa me pada kalimat tersebut bermakna
ikan hiu. Hal ini merujuk pada kalimat butir (b) yaitu ikan hiu adalah
teman bukan untuk dimakan. Merujuk pada konteks yang melingkupi
contoh (15), maka kedua kalimat tersebut dimaksudkan untuk
memerintah petutur agar turut serta melestarikan ikan hiu. Artinya
bahwa kalimat imperatif digunakan penutur untuk menyampaikan
pesan melalui pamflet secara langsung.
Contoh 16
Terapkan budaya buang sampah pada tempatnya.
Lokasi : MandatiPartisipan : LSM Kamelia, Dinas Kesehatan Kabupaten
Wakatobi, Pemerintah Daerah KabupatenWakatobi dan masyrakat pengunjung pasar
Waktu : 2017Konteks : Terminal pasar sentral Mandati.
Contoh (16) mencirikan jenis praanggapan faktif.
Praanggapan ini mengacu pada satuan bahasa terapkan. Penanda
ini bukanlah sebuah penanda umum yang dipaparkan sesuai dengan
teori di bab sebelumnya. Akan tetapi dapat dipahami bahwa
praanggapan faktif ini dapat hadir dalam sebuah pernyataan tanpa
adanya penanda-penanda umum dengan hadirnya penanda yang
menunjukan kefaktualan, dukungan konteks dan pemahaman
bersama. Seperti halnya penggunaan satuan bahasa terapkan
secara konvensional dapat dimaknai sebagai bentuk perintah untuk
76
mempraktikkan sesuatu. Secara keseluruhan contoh (16) bermakna
perintah untuk mempraktikkan budaya buang sampah pada
tempatnya. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya buang sampah
pada tempatnya belum diterapkan oleh kalangan masyarakat
Wakatobi.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (16) berbentuk
kalimat imperatif. Hal ini tampak pada penggunaan satuan bahasa
terapkan. Adapun penggunaan satuan bahasa terapkan secara
konvensional bermakna perintah atau ajakan untuk mempraktikkan
sesuatu. Jadi, LSM Kamelia, Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi,
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi sebagai penutur
bermaksud memerintah pengunjung pasar agar membuang sampah
pada tempatnya. Artinya bahwa kalimat imperatif digunakan penutur
untuk menyampaikan pesan melalui pamflet secara langsung.
Contoh 17
Bumi saja aku jaga, apalagi kamu.
Lokasi : Lapangan MerdekaPartisipan : LSM Kamelia, dan masyrakat peserta pawaiWaktu : 2017Konteks : hari bumi 2017. Pamflet dipegang oleh
perempuan dewasa.
Contoh (17) mencirikan praanggapan faktif, walaupun tidak
tampak penggunaan kata kerja yang menjadi ciri praanggapan faktif
dalam kontruksi kalimatnya. Kefaktualan suatu tuturan yang muncul
dalam praanggapan ini bisa juga dilihat dari partisipan tutur, konteks
77
situasi, dan juga pengetahuan bersama. Kontruksi kalimat tersebut
terdiri dari bumi saja aku jaga dan apalagi kamu. Pada satuan
bahasa bumi saja aku jaga bermakna aku menjaga bumi
(lingkungan) dan sesuatu selain bumi. Hal ini terlihat dari
penggunaan saja. Namun sesuatu selain bumi yang yang dimaksud
langsung disebutkan pada bagian akhir kalimat tersebut, yaitu
apalagi kamu. Satuan bahasa kamu merujuk pada pengunjung,
peserta, dan siapapun yang melihat kalimat tersebut. Mengingat
pemegang pamflet adalah perempuan dewasa, maka dapat
diasumsikan bahwa satuan bahasa kamu yang dimaksud adalah
lelaki dewasa.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (17) berbentuk
kalimat deklaratif. kalimat ini digunakan untuk memberitakan
sesuatu. Sebagaimana, kontruksi kalimat diatas yang terdiri dari
bumi saja aku jaga dan apalagi kamu. Pada satuan bahasa bumi
saja aku jaga bermakna aku menjaga bumi (lingkungan). Selanjutnya
pernyataan tersebut dikuatkan dengan hadirnya kata penghubung
apalagi sebagai penegasan suatu tindakan. Berdasarkan penjelasan
tersebut, maka contoh (17) bermaksud memerintah pengunjung
Lapangan Merdeka agar menjaga lingkungan. Artinya bahwa LSM
menyampaikan pesan melalui pamflet secara tak langsung. Hal ini
dilakukan oleh penutur agar petutur tidak merasa bahwa dirinya
diperintah.
78
Contoh 18
Mari selamatkan sumberdaya perikanan kita.
Lokasi : Perkampungan BajoPartisipan : Kementerian kelautan dan perikanan, dan
masyarakat bajoWaktu : 2017Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi di pos
kamling
Contoh (18) mencirikan praanggapan faktif. Praanggapan ini
mengacu pada penanda satuan bahasa mari selamatkan. Penanda
ini bukanlah sebuah penanda umum yang dipaparkan sesuai dengan
teori di bab sebelumnya. Akan tetapi dapat dipahami bahwa
praanggapan faktif dapat hadir dalam sebuah pernyataan tanpa
adanya penanda-penanda umum dengan hadirnya penanda yang
menunjukan kefaktualan, dukungan konteks dan pemahaman
bersama. Seperti halnya penggunaan satuan bahasa mari yang
bermakna kata seru untuk menyatakan ajakan. Selanjutnya satuan
bahasa selamatkan, secara konvensional satuan bahasa selamatkan
adalah bentuk perintah yang berarti menyuruh membebaskan dari
bahaya. Selain itu, sumber daya perikanan merupakan salah satu
sektor andalan Pemda Wakatobi belum dikelola secara maksimal
terutama pengawasan. Hal ini terbukti masih banyak ditemukan
pelanggaran yang dilakaukan oleh nelayan berupa penggunaan alat
tangkap tak ramah lingkungan. Berdasarkan penjelasan tersebut
dapat dipahami bahwa praanggapannya yakni sumberdaya
79
perikanan sedang terancam dan butuh penanggulangan secara
serius.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (18) berbentuk
kalimat imperatif. Hal ini tampak pada penggunaan satuan bahasa
mari dan selamatkan. Satuan bahasa mari bermakna kata seru untuk
menyatakan ajakan. Selanjutnya, satuan bahasa selamatkan
bermakna perintah atau ajakan agar terbebas dari bahaya. Dengan
demikian satuan bahasa mari selamatkan pada contoh (18) dapat
dipahami bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai
penerbit pamflet berupaya mengajak petutur (masyarakat bajo) agar
memelihara sumberdaya perikanan. Artinya bahwa kalimat imperatif
digunakan penutur untuk menyampaikan pesan melalui pamflet
secara tak langsung.
Contoh 5
(a) Tak kenal maka tak sayang.(b) Lihatlah lebih dalam.(c) Lestarikan kekayaan lautmu.
Lokasi : perkampungan BajoPartisipan : LSM, dan masyarakat BajoWaktu : 2017Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi di
pelabuhan nelayan. Pelabuhan selalu ramaididatangi oleh masyarakat bajo yangmenunggu kerabat mereka pulang darimelaut. Selain itu banyak juga kalanganpenjual ikan yang menunggu nelayan danhendak membeli hasil tangkapannya. Isipamflet disertai gambar ikan-ikan dan terumbukarang.
80
Contoh (5) butir (c) mencirikan praanggapan faktif.
Praanggapan ini mengacu pada penanda satuan bahasa lestarikan.
Penanda ini bukanlah sebuah penanda umum yang dipaparkan
sesuai dengan teori pada bab sebelumnya. Akan tetapi dapat
dipahami bahwa praanggapan faktif dapat hadir dalam sebuah
pernyataan tanpa adanya penanda-penanda umum dengan hadirnya
penanda yang menunjukan kefaktualan, dukungan konteks dan
pemahaman bersama. Seperti halnya penggunaan satuan bahasa
lestarikan. Secara konvensional satuan bahasa lestarikan bermakna
ajakan atau perintah untuk menjaga tetap seperti keadaannya
semula.
Selain itu, pamflet pada contoh tersebut dipajang di pusat
informasi pelabuhan nelayan yang sehari-hari selalu ramai, baik
nelayan maupun masyarakat yang akan memebeli ikan. Hal ini
dapat dipahami bahwa pernyataan dalam pamflet ditujukan kepada
masyarakat khususnya nelayan agar turut serta menjaga kelestarian
laut. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukan bahwa
penggunaan satuan bahasa lestarikan bermakna adanya kondisi
kekayaan laut membutuhkan penanganan atau pelestarian.
Sehingga praanggapannya yakni kekayaan laut sedang tidak baik.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (5) butir (c)
berbentuk kalimat imperatif. Penanda kalimat imperatif pada butir (c)
tampak pada penggunaan satuan bahasa lestarikan. Secara
81
konvensional satuan bahasa lestarikan bermakna ajakan atau
perintah untuk menjaga tetap seperti keadaannya semula. Senada
dengan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penutur bermaksud
memerintah petutur khususnya masyarakat Bajo agar menjaga
kelestarian kekayaan laut. Artinya bahwa kalimat imperatif digunakan
penutur untuk menyampaikan pesan melalui pamflet secara
langsung.
Contoh 8
(a) Terimakasih atas partisipasinya dalam melestarikanterumbu karang.
(b) Terumbu karang sehat, ikan berlimpah, masyarakatsejahtera.
Lokasi : Pasar Pagi WanciPartisipan : Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Coremap II, dan pengunjung pasarWaktu : 2017Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi
Praanggapan faktif pada contoh (8) terdapat pada butir (a).
Hal ini tampak pada penggunaan satuan lingual melestarikan pada
butir (a). Satuan lingual tersebut merupakan kata kerja yang diikuti
informasi yang dipraanggpakan. Selain itu, informasi yang
dipraanggapkan menjadi faktual diperkuat oleh satuan lingual terima
kasih pada butir (a). Artinya, terima kasih bermakna bentuk
penghargaan atas terealisasinya suatu tindakan melestarikan
terumbu karang. Butir (b) merupakan pernyataan hubungan
kausalitas dengan butir (a). Pada konteks ini, butir (b) sebagai
penegasan betapa pentingnya pelestarian terumbu karang. Melalui
82
penjelasan tersebut dapat diketahui praanggapannya yaitu
masyarakat berpartisipasi melestarikan terumbu karang.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (8) butir (a)
berbentuk kalimat ekslamatif. Penanda kalimat ekslamatif pada butir
(a) tampak pada penggunaan satuan bahasa terima kasih dan
partikel –nya pada satuan bahasa partisipasi. Satuan bahasa terima
kasih bermakna mengucap syukur; melahirkan rasa syukur atau
membalas budi setelah menerima kebaikan dan sebagainya.
Adapun satuan bahasa partisipasinya bermakna keikutsertaan yang
telah dilakukan. Secara lengkap, kalimat pada butir (a) dapat
dipahami bahwa rasa terimakasih ditujukan kepada pengunjung
pasar yang senantiasa menjaga kelestarian terumbu karang.
Berkenaan dengan penjelasan tersebut maka, kalimat ekslamatif
pada butir (a) bermaksud memberi pujian atau apresiasi kepada
masyarakat yang telah menjaga terumbu karang sekaligus menyindir
masyarakat yang belum melakukan hal serupa agar tersentuh untuk
menjaga terumbu karang. Artinya bahwa kalimat ekslamatif
digunakan penutur untuk menyampaikan pesan melalui pamflet
secara tak langsung. Hal ini dilakukan oleh penutur agar mitra tutur
tidak merasa bahwa dirinya diperintah.
Penjelasan tersebut dapat digambarkan penggunaan bentuk
kalimat dan maksud pada tiap-tiap praanggapan faktif. Hal ini dapat
dilihat pada tabel 4.2. berikut ini.
83
Tabel 4.2. Penggunaan bentuk kalimat pada praanggapan faktif
Contoh
Bentuk Kalimat
MaksudDek Imp Int Eks
(13) Selamatkan laut indonesia darisampah karena laut masa depan bangsa.
+ memerintah
(14.a) Save Turtle. + memerintah
(14.b) Lestarikan penyu dan jangan jadikanmereka buruan.
+ memerintah
(15.a) Save me guys. + memerintah
(16) Terapkan budaya buang sampah padatempatnya.
+ memerintah
(17) Bumi saja aku jaga, apalagi kamu. + memerintah
(18) Mari selamatkan sumberdayaperikanan kita.
+ mengajak
(5.c) Lestarikan kekayaan lautmu. + memerintah
(8.a) Terimakasih atas partisipasinya dalammelestarikan terumbu karang.
+ mengapresiasi
Jumlah 1 7 - 1
Pada tabel (4.2.) tampak bahwa terdapat sembilan
praanggapan faktif. Paraanggapan tersebut dominan direalisasikan
dengan menggunakan kalimat imperatif. Adapun maksud dari
keseluruhan praanggapan tersebut yaitu: memerintah,
mengapresiasi, dan mengajak.
3. Praanggapan Leksikal
Praanggapan leksikal dipahami sebagai bentuk praanggapan
yang menyatakan makna secara konvensional ditafsirkan dengan
praanggapan bahwa suatu makna lain (yang tidak dinyatakan)
dipahami. Terdapat beberapa satuan bahasa yang digunakan
84
sebagai penanda dalam praanggapan leksikal ini seperti “memulai,
menyelesaikan, melanjutkan, membawa, meninggalkan, berhenti”.
Contoh 2
(a)Wakatobi bersih tanpa sampah.(b)Stop buang sampah ke laut.
Lokasi : Pantai MarinaPartisipan : LSM Kamelia, dan masyrakat pengunjung
Pantai MarinaWaktu : 2017Konteks : pamflet dipegang oleh anak sekolah dasar
(SD) pada saat senam pagi.
Praanggapan leksikal pada contoh (2) terdapat pada butir (b).
Praanggapan ini mengacu pada penanda satuan bahasa stop.
Satuan bahasa stop (bahasa inggris) berarti penghentian atau
berhenti sehingga dapat diketahui praanggapannya bahwa
sebelumnya sering terjadi tindakan buang sampah ke laut atau
tingkat kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan masih
rendah.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (2) butir (b)
berbentuk kalimat imperatif. Hal ini ditandai dengan penggunaan
satuan bahasa stop yang bermakna penghentian atau hentikan.
Pamflet pada contoh (2) diterbitkan oleh LSM Kamelia, namun dalam
upaya menyosialisasikan pelestarian lingkungan melibatkan anak-
anak dengan maksud pesan yang disampaikan tercapai. Peran
anak-anak dalam konteks ini sangatlah penting sebab dapat
menghasilkan beberapa manfaat. Manfaat tersebut diantaranya:
85
pendidikan anak sejak dini, memicu perhatian, dan pengaruh
psikologis kepada orang dewasa. Artinya bahwa kalimat imperatif
digunakan penutur untuk menyampaikan pesan melalui pamflet
secara langsung.
Dari penjelasan tersebut dapat digambarkan penggunaan
bentuk kalimat dan maksud pada tiap-tiap praanggapan leksikal. Hal
ini dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut ini.
Tabel 4.3. Penggunaan bentuk kalimat pada praanggapan leksikal
Contoh
Bentuk Kalimat
MaksudDek Imp Int Eks
(2.b) Stop buang sampah ke laut. + memerintah
Jumlah 1 - - -
Pada tabel (4.3.) tampak bahwa hanya satu praanggapan
leksikal. Paraanggapan tersebut direalisasikan dengan
menggunakan kalimat imperatif. Adapun maksud praanggapan
tersebut adalah memerintah.
4. Praanggapan Struktural
Praanggapan struktural adalah praanggapan yang secara
tetap dan konvensional bahwa bagian struktur itu sudah diasumsikan
kebenarannya. Dengan kata lain praanggapan ini dinyatakan dengan
tuturan yang strukturnya jelas dan langsung dipahami tanpa melihat
kata-kata yang digunakan. Hal ini tampak dalam kalimat tanya,
secara konvensional diinterpretasikan dengan kata tanya (kapan dan
86
di mana) sesudah diketahui sebagai masalah, pertanyaan alternatif
(Alternative Question), dan pertanyaan ya/tidak (Yes/No Question).
Penggunaan praanggapan struktural dapat dilihat pada contoh
berikut ini.
Contoh 22
(a) Kalian boleh tangkap kami, tapi kalian harus lestarikanrumah kami.
(b) Bagaimana??(c) Deal??
Lokasi : Pasar Pagi WanciPartisipan : Kementerian kelautan dan perikanan,
Lingkungan Hidup, LSM Coremap II, danmasyrakat pengunjung pasar
Waktu : 2017Konteks : pamflet dipajang pada pos informasi pasar
ikan. Pamflet bergambar ikan-ikan danterumbu karang
Praanggapan struktural pada contoh (22) terdapat pada butir
(b) dan butir (c). Hal ini tampak pada penggunaan satuan bahasa
bagaimana dan diikuti tanda tanya (?). Satuan bahasa bagaimana
bermakna kata tanya untuk menanyakan cara atau perbuatan.
Sebagaimana ciri praanggapan struktural yaitu mengandung
pertanyaan alternatif. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat
dipahami bahwa satuan bahasa bagaimana? bermakna pertanyaan
yang memberikan alternatif dari dua kemungkinan sebagaimana
pada butir (a) yaitu kalian boleh tangkap kami dan kalian harus
lestarikan rumah kami. Adapun praanggapan struktural pada butir (c)
ditandai oleh penggunaan tanda tanya (?) yang mengikuti satuan
87
bahasa deal. Satuan bahasa deal (bahasa inggris) berarti janji atau
perjanjian. Secara konvensional, penggunaan satuan bahasa deal?
dapat dimaknai pertanyaan yang diajukan dengan mengharapkan
jawaban ya atau tidak. Dengan demikian butir (c) memenuhi ciri
praanggapan struktural yaitu mengandung pertanyaan ya/tidak.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (22) butir (b) dan
butir (c), keduanya berbentuk kalimat interogatif. Hal ini tampak pada
penggunaan kata tanya dan tanda tanya (?). Pada butir (b) bentuk
bagaimana bermakna kata tanya untuk menanyakan cara atau
perbuatan sebagaimana pada butir (a). Pada butir (c) deal berarti
perjanjian, jika ditambahkan tanda tanya (?) maka maknanya yaitu
menanyakan kesepakatan perjanjian sebagaimana pada butir (a).
Secara umum butir (a) dapat dipahami bahwa penerbit pamflet
membolehkan masyarakat menangkap ikan dengan syarat
menunaikan kewajiban memelihara terumbu karang yang merupakan
rumah bagi ikan-ikan. Artinya bahwa kewajiban memelihara terumbu
karang pada konteks kalimat tersebut hanya dikenakan kepada
masyarakat yang menangkap ikan. Berdasarkan penjelasan
tersebut, maka contoh (22) butir (b) dan (c) bermaksud memerintah
pengunjung pasar ikan agar melestarikan terumbu karang. Artinya
bahwa penutur menyampaikan pesan melalui pamflet secara tak
langsung. Hal ini dilakukan oleh penutur agar petutur tidak merasa
bahwa dirinya diperintah.
88
Contoh 11
(a) Sadarkah anda?(b) Betapa berharganya mereka jika sudah dikelola(a) Kenali potensi dan peluang investasi pulau-pulau kecil
indonesia
Lokasi : Pasar Sore, WanciPartisipan : Coremap II, WWF, RARE, dan pengunjung
pasarWaktu : 2017Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi dekat
penjualan ikan
Praanggapan struktural pada contoh (11) terdapat pada butir
(a). Sebagaimana diketahui bahwa praanggpan struktural mengacu
pada struktur kalimat telah dianalisis sebagai praanggapan secara
tetap dan konvensiaonal bahwa bagian struktur itu sudah
diasumsikan kebenarannya. Hal ini tampak pada penggunaan satuan
bahasa sadarkah dan diakhiri tanda tanya (?). Satuan bahasa
sadarkah anda? merupakan bentuk pertanyaan yang diajukan
dengan mengharapkan jawaban ya atau tidak. Dengan demikian
butir (c) memenuhi ciri praanggapan struktural yaitu mengandung
pertanyaan ya/tidak.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (11) butir (a)
berbentuk kalimat interogatif. Satuan bahasa sadar pada butir (a)
bermakna ingat kembali; tahu; dan mengerti, dan mendapat partikel -
kah yang berarti penanda kata tanya. Selain itu terdapat penggunaan
tanda tanya (?) pada akhir kalimat sebagai ciri kalimat interogatif.
Jadi kalimat sadarkah anda? bermakna pertanyaan kepada anda
untuk mengingat kembali sesuatu. Pada butir (b) betapa
89
berharganya mereka jika di kelola merupakan penjelasan dari butir
(a). Demikian halnya pada butir (c) kenali potensi dan peluang
investasi pulau-pulau kecil melengkapi penjelasan butir (b). Satuan
lingual mereka pada butir (b) merujuk pada butir (c) yaitu pulau-pulau
kecil.
Berdasarkan penjelasan tersebut dan merujuk pada konteks
yang melingkupi pamflet dapat dipahami bahwa contoh (11) butir (a)
berbentuk kalimat interogatif yang bermaksud menyegarkan
pengetahuan sekaligus meberitakan masyarakat tentang pentingnya
pengelolaan pulau-pulau kecil. Artinya bahwa kalimat interogatif
digunakan penutur untuk menyampaikan pesan melalui pamflet
secara tak langsung.
Contoh 12
(a) Tahukah kamu laut indonesia sangat kaya?(b) Ikan melimpah nelayan sejahtera.
Lokasi : Pasar sentral,MandatiPartisipan : Coremap II, WWF, RARE, dan pengunjung
pasarWaktu : 2017Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi dekat
terminal
Praanggapan struktural pada contoh (12) terdapat pada butir
(a). Sebagaimana diketahui bahwa praanggpan struktural mengacu
pada struktur kalimat telah dianalisis sebagai praanggapan secara
tetap dan konvensiaonal bahwa bagian struktur itu sudah
diasumsikan kebenarannya. Hal ini tampak dalam kalimat tanya
pada butir (a) yang diinterpretasikan dengan kata tanya tahukah
90
diketahui sebagai masalah dan diakhiri dengan tanda tanya (?).
Dengan kata lain praanggapan ini dinyatakan dengan kalimat yang
strukturnya jelas dan langsung dipahami tanpa melihat kata-kata
yang digunakan. Penjelasan tersebut menunjukkan praanggapan
yaitu laut indonesia sangat kaya. Praanggapan yang menyatakan
‘kebenaran’ sebagai bahan pembicaraan yang dipahami oleh penutur
melalui struktur kalimat tanya yang menanyakan tahukah.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (12) butir (a)
berbentuk kalimat interogatif. Hal ini tampak pada penggunaan
patikel –kah pada kata tahu dan diakhiri dengan tanya tanya (?).
pada butir (a) satuan bahasa tahu bermakna kenal; mengerti
sesudah mengalami dan mendapat partikel -kah yang berarti
penanda kata tanya. Pada butir (a) sangat kaya merujuk pada butir
(b) ikan melimpah. Berdasarkan penjelasan tersebut dan merujuk
pada konteks yang melingkupi pamflet dapat dipahami bahwa contoh
(12) butir (a) berbentuk kalimat interogatif yang bermaksud
meberitakan kekayaan laut indonesia dan dampaknya bagi
masyarakat sehingga masyarakat berpartisipasi menjaga kelestarian
ikan. Artinya bahwa kalimat interogatif digunakan penutur untuk
menyampaikan pesan melalui pamflet secara tak langsung.
Dari penjelasan tersebut dapat digambarkan penggunaan
bentuk kalimat dan maksud pada tiap-tiap praanggapan struktural.
Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut ini.
91
Tabel 4.4. Penggunaan bentuk kalimat pada praanggapan struktural
Contoh
Bentuk Kalimat
MaksudDek Imp Int Eks
(22.b) Bagaimana?? + memerintah
(22.c) Deal??. + memerintah
(11.a) Sadarkah anda? + memerintah
(12.a) Tahukah kamu laut indonesia sangatkaya?
+ memerintah
Jumlah - - 4 -
Pada tabel (4.4.) tampak bahwa terdapat empat praanggapan
struktural. Paraanggapan tersebut direalisasikan dengan
menggunakan kalimat interogatif. Adapun maksud dari keseluruhan
praanggapan tersebut adalah memerintah.
5. Praanggapan Konterfaktual
Praanggapan konterfaktual berarti bahwa yang
dipraanggapkan tidak hanya tidak benar, tetapi juga merupakan
kebalikan (lawan) dari benar atau bertolak belakang dengan
kenyataan. Praanggapan ini menghasilkan pemahaman yang
berkelebihan dari pernyataannya atau kontradiktif. Hasil yang didapat
menjadi kontradiktif dari pernyataan sebelumnya. Penggunaan
praanggapan konterfaktual dapat dilihat pada contoh berikut ini.
Contoh 15
(a) Save me guys.(b) Ikan hiu adalah teman bukan untuk dimakan.
Lokasi : Pantai MarinaPartisipan : LSM Kamelia, dan masyrakat pengunjung
92
Pantai MarinaWaktu : 2017Konteks : pamflet dipegang oleh anak sekolah dasar
(SD) pada saat senam pagi.
Contoh (15) butir (b) mencirikan praanggapan konterfaktual.
Praanggapan ini mengacu pada kalimat yang dipraanggapkan tidak
hanya tidak benar, tetapi juga merupakan kebalikan (lawan) dari
benar atau bertolak belakang dengan kenyataan. Pada contoh
tersebut kalimat yang dipraanggapkan yaitu ikan hiu adalah teman.
Pernyataan ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa
masyarakat wakatobi kerap melakukan perburuan terhadap ikan hiu
sebagai kebutuhan makanan. Berdasarkan penjelasan tersebut
dapat diketahui praanggapannya yaitu masyarakat sering makan
ikan hiu.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (15) butir (b)
berbentuk kalimat deklaratif. Hal ini tampak pada konten kalimat
berupa pernyataan. Sebagai penandanya yaitu satuan bahasa
adalah, kemudian diikiuti oleh informasi penjelasan teman bukan
untuk dimakan. Pamflet pada contoh (15) butir (b) diterbitkan oleh
LSM Kamelia, namun dalam upaya menyosialisasikan pelestarian
lingkungan melibatkan anak-anak dengan maksud pesan yang
disampaikan tercapai. Peran anak-anak dalam konteks ini sangatlah
penting sebab dapat menghasilkan beberapa manfaat. Manfaat
tersebut diantaranya: pendidikan anak sejak dini, memicu perhatian,
dan pengaruh psikologis kepada orang dewasa.
93
Jadi, merujuk pada konteks yang melingkupi contoh (15) butir
(b), maka kalimat tersebut dimaksudkan untuk memerintah petutur
agar menjaga kelestarian ikan hiu. Artinya bahwa LSM
menyampaikan pesan melalui pamflet secara tak langsung. Hal ini
dilakukan oleh penutur agar petutur tidak merasa bahwa dirinya
diperintah.
Contoh 20
Penyu adalah sahabat bukan untuk dimakan.
Lokasi : Pantai MarinaPartisipan : LSM Kamelia, dan masyarakat pengunjung
Pantai MarinaWaktu : 2017Konteks : pamflet dipegang oleh anak sekolah dasar
(SD) pada saat senam pagi.
Contoh (20) mencirikan praanggapan konterfaktual.
Praanggapan ini mengacu pada kalimat yang dipraanggapkan tidak
hanya tidak benar, tetapi juga merupakan kebalikan (lawan) dari
benar atau bertolak belakang dengan kenyataan. Pada contoh
tersebut kalimat yang dipraanggapkan yaitu penyu adalah sahabat.
Pernyataan ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa
masyarakat wakatobi kerap melakukan perburuan terhadap penyu
sebagai kebutuhan makanan. Berdasarkan penjelasan tersebut
dapat diketahui praanggapannya yaitu masyarakat sering makan
penyu.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (20) berbentuk
kalimat deklaratif. Hal ini tampak pada konten kalimat berupa
94
pernyataan. Sebagai penandanya yaitu satuan bahasa adalah,
kemudian diikuti oleh informasi penjelasan sahabat bukan untuk
dimakan. Pamflet pada contoh (20) diterbitkan oleh LSM Kamelia,
namun dalam upaya menyosialisasikan pelestarian lingkungan
melibatkan anak-anak dengan maksud pesan yang disampaikan
tercapai. Peran anak-anak dalam konteks ini sangatlah penting
sebab dapat menghasilkan beberapa manfaat. Manfaat tersebut
diantaranya: pendidikan anak sejak dini, memicu perhatian, dan
pengaruh psikologis kepada orang dewasa.
Jadi, merujuk pada konteks yang melingkupi contoh (20) butir
(b), maka kalimat tersebut dimaksudkan untuk memerintah petutur
agar menjaga kelestarian penyu. Artinya bahwa LSM menyampaikan
pesan melalui pamflet secara tak langsung. Hal ini dilakukan oleh
penutur agar petutur tidak merasa bahwa dirinya diperintah.
Contoh 19
(a) Kalian boleh tangkap kami, tapi kalian harus lestarikanrumah kami.
(b) Bagaimana??(a) Deal??
Lokasi : Pasar Pagi WanciPartisipan : Kementerian kelautan dan perikanan,
Lingkungan Hidup, LSM Coremap II, danmasyrakat pengunjung pasar
Waktu : 2017Konteks : pamflet dipajang pada pos informasi pasar
ikan. Pamflet bergambar ikan-ikan danterumbu karang
Contoh (19) mencirikan praanggapan konterfaktual.
Praanggapan konterfaktual berarti bahwa yang dipraanggapkan tidak
95
hanya tidak benar, tetapi juga merupakan kebalikan (lawan) dari
benar atau bertolak belakang dengan kenyataan. Hal ini tampak
pada butir (a) kalian boleh tangkap kami, tapi kalian harus lestarikan
rumah kami. Bentuk kalian merujuk pada nelayan, kami merujuk
pada ikan-ikan, dan rumah kami merujuk pada terumbu karang.
Pada bagian awal kalimat yakni kalian boleh tangkap kami bermakna
nelayan diizinkan menangkap ikan. Selanjutnya pada bagian akhir
kalimat yakni tapi kalian harus lestarikan rumah kami bermakna
prasyarat untuk menangkap ikan (bagian awal kalimat) yaitu
memelihara terumbu karang. Hal ini ditandai dengan penggunaan
bentuk tapi (tetapi) yang bermakna kata penghubung intrakalimat
untuk menyatakan hal yang bertentangan.
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditemukan
praanggapan yang muncul adalah nelayan tidak melestarikan
lingkingan. Praanggapan tersebut muncul dari kontradiksi kalimat
dengan adanya penggunaan bentuk tapi. Penggunaan tapi membuat
praanggapan yang kontradiktif dari kalimat yang disampaikan.
Bentuk kalimat yang digunakan pada contoh (19) butir (a)
berbentuk kalimat imperatif. Hal ini tampak pada penggunaan satuan
bahasa harus lestarikan. Satuan bahasa kalian merujuk pada
nelayan, satuan bahasa boleh bermakna diizinkan, satuan bahasa
harus bermakna wajib, mesti (tidak boleh tidak), dan satuan bahasa
lestari bermakna tetap seperti keadaannya semula. Adapun
96
penggunaan satuan lingual lestarikan bermakna perintah atau ajakan
untuk menjaga tetap seperti keadaannya semula. Jadi satuan
bahasa harus lestarikan bermakna kewajiban menjaga sesuatu tetap
seperti keadaannya semula. Lalu satuan bahasa kami pada akhir
kalimat merujuk pada ikan-ikan. Secara umum butir (a) dapat
dipahami bahwa penerbit pamflet membolehkan masyarakat
menangkap ikan dengan syarat menunaikan kewajiban memelihara
terumbu karang yang merupakan rumah bagi ikan-ikan. Artinya
bahwa kewajiban memelihara terumbu karang pada konteks tersebut
hanya dikenakan kepada masyarakat yang menangkap ikan.
Berkaitan dengan penjelasan tersebut, maka contoh (19)
digunakan oleh penutur untuk membolehkan masyarakat menangkap
ikan. Selain itu, kalimat tersebut juga dimaksudkan untuk
memerintah petutur (pengunjung pasar) untuk melestarikan terumbu
karang. Artinya bahwa kalimat imperatif digunakan penutur untuk
menyampaikan pesan melalui pamflet secara langsung.
Dari penjelasan tersebut dapat digambarkan penggunaan
bentuk kalimat dan maksud pada tiap-tiap praanggapan
konterfaktual. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut ini.
Tabel 4.5. Penggunaan bentuk kalimat pada praanggapan konterfaktual
Contoh
Bentuk Kalimat
MaksudDek Imp Int Eks
(15.b) Ikan hiu adalah teman bukanuntuk dimakan.
+ Memerintah
97
(20) Penyu adalah sahabat bukan untukdimakan.
+ Memerintah
(19.a) Kalian boleh tangkap kami, tapikalian harus lestarikan rumah kami.
+ Memerintah
Jumlah 2 1 - -
Pada tabel (4.5.) tampak bahwa terdapat tiga praanggapan
konterfaktual. Paraanggapan tersebut dominan direalisasikan
dengan menggunakan kalimat deklaratif. Adapun maksud dari
keseluruhan praanggapan tersebut adalah memerintah.
B. Penggunaan Praanggapan, Bentuk Kalimat dan Maksud Kalimat
pada Tiap-tiap Penerbit Pamflet Sosialisasi Pelestarian
Lingkungan di Kabupaten Wakatobi
Upaya pelestarian lingkungan di kabupaten Wakatobi melalui
pamflet dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan
Pemerintah. Pada penelitian ini, LSM yang menerbitkan pamflet yaitu:
komunitas melihat alam (Kamelia), Corremap, Rare, dan WWF,
sedangkan dari pemerintah yaitu: Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Wakatobi. Selain itu, ditemukan juga pamflet yang diterbitkan
secara kolektif oleh LSM dan pemerintah. Berikut ini uraiannya.
1. Lembaga Swadaya Masyarakat
Sesuai dengan hasil analisis praanggapan, bentuk kalimat,
dan maksud kalimat yang telah dipaparkan sebelumnya, maka
penggunaan praanggapan, bentuk kalimat, dan maksud kalimat dari
98
setiap pamflet yang diterbitkan oleh LSM dapat digambarkan pada
tabel 4.6 dibawah ini.
Tabel 4.6. Rekapitulasi penggunaan praanggapan dan bentuk kalimatpada pamflet yang diterbitkan LSM.
Contoh Praanggapan Bentuk kalimat MaksudPE PF PL PN PS PK Dek Imp Int Eks
(1.a) + + Memerintah(1.b) - + Memerintah(2.a) + + Memerintah(2.b) + + Memerintah(3) + + Memerintah(4) + + Memerintah(5.a) + - Memerintah(5.b) + + Memerintah(5.c) + + Memerintah(6.a) + + Memerintah(6.b) + + Memerintah(9.a) + + Memerintah(9.b) + + Memerintah(10.a) + + Memerintah(10.b) + + Memerintah(11.a) + + Memerintah(11.b) + + Membujuk(11.c) + + Memerintah(12.a) + + Memerintah(12.b) + + Memerintah(14.a) + + Memerintah(14.b) + + Memerintah(15.a) + + Memerintah(15.b) + + Memerintah(17) + + Memerintah(20) + + MemerintahTotal 15 5 1 - 2 2 7 14 2 2(%) 57,7 19,2 3,8 7,7 7,7Dengan Total Praanggapan= 26 (100%)
Pada tabel (4.6.) tampak bahwa LSM menerbitkan 14 pamflet
dan terdiri dari 26 kalimat . Praanggapan yang digunakan yaitu:
57,7% praanggapan eksistensial, 19,2% praanggapan faktif, 3,8%
praanggapan leksikal, 7,7% praanggapan struktural, 7,7%
99
praanggapan konterfaktual. Bentuk kalimat yang digunakan yaitu:
tujuh kalimat deklaratif, empat belas kalimat imperatif, dua kalimat
interogatif, dan dua kalimat ekslamatif. Maksud kalimat tersebut
dominan untuk memerintah.
Berdasarkan uraian tersebut, maka terlihat bahwa
praanggapan eksistensial merupakan praanggapan yang dominan
digunakan oleh LSM. Ditinjau berdasarkan kelangsungan dan
ketaklangsungan kalimatnya, maka LSM menggunakan tiga belas
kalimat langsung dan dua belas kalimat tak langsung.
2. Pemerintah
Sesuai dengan hasil analisis praanggapan, bentuk kalimat,
dan maksud kalimat yang telah dipaparkan sebelumnya, maka
penggunaan praanggapan, bentuk kalimat, dan maksud kalimat dari
setiap pamflet yang diterbitkan oleh pemerintah dapat digambarkan
pada tabel 4.7 dibawah ini.
Tabel 4.7. Rekapitulasi penggunaan praanggapan dan bentuk kalimatpada pamflet yang diterbitkan Pemerintah.
Contoh Praanggapan Bentuk kalimat MaksudPE PF PL PN PS PK Dek Imp Int Eks
(7) + + Memerintah(13) + + Memerintah(18) + + MengajakTotal 1 2 - - - - - 3 - -(%) 33,3 66,7Dengan Total Praanggapan= 3 (100%)
100
Pada tabel (4.7.) tampak bahwa pemerintah menerbitkan tiga
pamflet yang terdiri dari tiga kalimat. Praanggapan yang digunakan
yaitu: 33,3% praanggapan eksistensial dan 66,7% praanggapan
faktif. Ketiga kalimat tersebut menggunakan bentuk kalimat imperatif
yang dimaksudkan memerintah dan mengajak. Berdasarkan uraian
tersebut, maka terlihat bahwa praanggapan faktif merupakan
praanggapan yang dominan digunakan oleh pemerintah. Ditinjau
berdasarkan kelangsungan dan ketaklangsungan kalimatnya, maka
pemerintah menggunakan kalimat langsung.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah
Sesuai dengan hasil analisis praanggapan, bentuk kalimat,
dan maksud kalimat yang telah dipaparkan sebelumnya, maka
penggunaan praanggapan, bentuk kalimat, dan maksud kalimat dari
setiap pamflet yang diterbitkan oleh LSM dan pemerintah dapat
digambarkan pada tabel 4.8 dibawah ini.
Tabel 4.8. Rekapitulasi penggunaan praanggapan dan bentuk kalimatpada pamflet yang diterbitkan LSM dan Pemerintah .
Contoh Praanggapan Bentuk kalimat MaksudPE PF PL PN PS PK Dek Imp Int Eks
(8.a) + + mengapresiasi(8.b) + + Memerintah(16) + + Memerintah(19.a) + + Memerintah(19.b) + + Memerintah(19.c) + + Memerintah
Total 1 2 - - 2 1 1 2 2 1(%) 16,7 33,3 33,3 16,7Dengan Total Praanggapan= 6 (100%)
101
Pada tabel (4.8.) tampak bahwa LSM dan pemerintah
menerbitkan 3 pamflet secara kolektif yang terdiri dari enam kalimat.
Praanggapan yang digunakan yaitu: 16,7% praanggapan
eksistensial, 33,3% praanggapan faktif, 33,3% praanggapan
struktural, dan 16,7% praanggapan konterfaktual. Bentuk kalimat
yang digunakan yaitu: satu kalimat deklaratif, dua kalimat imperatif,
dua kalimat interogatif, dan satu kalimat ekslamatif. Maksud kalimat
tersebut dominan untuk memerintah. Ditinjau berdasarkan
kelangsungan dan ketaklangsungan kalimatnya, maka LSM dan
pemerintah menggunakan dua kalimat langsung dan empat kalimat
tak langsung.
102
BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil uraian dan analisis data, dapat disimpulkan
beberapa hal yang menjadi temuan dalam penelitian ini. Adapun jumlah
pamflet pada penelitian ini yaitu 20 pamflet yang terdiri dari 35 kalimat.
Temuan tersebut terkait dengan dua tujuan utama penelitian ini, yaitu (1)
Jenis praanggapan dan bentuk kalimat, (2) penggunaan praanggapan,
bentuk kalimat dan maksud kalimat pada tiap-tiap penerbit pamflet yakni
LSM dan pemerintah. Kedua simpulan tersebut dapat diuraikan berikut ini.
Pertama, praanggapan yang terdapat pada pamflet sosialisasi
pelestarian lingkungan di Kabupaten Wakatobi terdiri atas empat jenis,
yaitu 48,6% praanggapan eksistensial, 25,7% praanggapan faktif, 2,8%
praanggapan leksikal, 11,4% praanggapan struktural, dan 8,6%
praanggapan konterfaktual sedangkan praanggapan nonfaktif tidak
ditemukan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerbit pamflet di Wakatobi
baik pemerintah maupun LSM berusaha menyosialisasikan pelestarian
lingkungan secara riil. Artinya bahwa penerbit pamflet tidak menggunakan
praanggapan nonfaktif yang notabene sebagai suatu praanggapan yang
diasumsikan tidak benar atau memungkinkan adanya pemahaman yang
salah karena penggunaan kata-kata yang tidak pasti atau ambigu. Dalam
konteks tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah dan LSM sangat
serius menangani permasalahan lingkungan. Adapun Bentuk kalimat yang
103
digunakan pada pamflet sosialisasi pelestarian lingkungan di Kabupaten
Wakatobi terdiri atas empat jenis, yaitu (1) kalimat deklaratif, (2) kalimat
interogatif, (3) kalimat imperatif, dan (4) kalimat ekslamatif. Sedangkan
keseluruhan maksud pengutaraannya untuk memerintah, membujuk,
mengajak, dan mengapresiasi.
Kedua, pengunaan praanggapan, bentuk kalimat dan maksud
pamflet sosialisasi pelestarian lingkungan di Kabupaten Wakatobi terdapat
pada LSM dan pemerintah. LSM dominan menggunakan praanggapan
eksistensial dan direalisasikan dengan kalimat deklaratif, kalimat imperatif,
kalimat interogatif, dan kalimat ekslamatif yang bermaksud memerintah,
membujuk, dan mengapresiasi sedangkan pemerintah dominan
menggunakan praanggapan faktif dan direalisasikan dengan kalimat
imperatif saja yang bermaksud memerintah dan mengajak. Secara
keseluruhan bentuk kalimat yang dominan digunakan yakni kalimat
imperatif yang dimaksudkan untuk memerintah. Hal ini menunjukan bahwa
pemerintah dan LSM menyosialisasikan pelestarian lingkungan di
Kabupaten Wakatobi menggunakan kalimat langsung (secara terus
terang).
B. Saran
Berdasarkan simpulan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya
maka berikut ini disampaikan beberapa saran yang berkorelasi dengan
hasil penelitian ini.
104
Pertama, tujuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan
pengembangan dan pengajaran ilmu pragmatik, terutama pada teori
praanggapan (presupposition). Penggunaan temuan dalam penelitian ini
diharapkan dapat menjadi acuan dan selanjutnya dilakukan
penyempurnaan teori praanggapan dalam berbahasa dan ilmu pragmatik
itu sendiri. Oleh karena itu, disarankan kepada penulis lain yang ingin
meneliti yang ada kaitannya dengan penggunaan praanggapan berikut
bentuk kalimat pada pamflet untuk mengembangkannya lagi, misalnya
implikatur dan efektifitas pamflet.
Kedua, kajian mengenai praanggapan pada pamflet sosialisasi
pelestarian lingkungan di Kabupaten Wakatobi menggunakan jenis-jenis
praanggapan yang menunjukan eksistensi dan kondisi riil perihal
permasalah lingkungan. Adapun penggunaan kalimat disampaikan secara
terus terang atau cenderung represif. Oleh karena itu hendaknya
pemerintah dan LSM menggunakan bentuk-bentuk kalimat fungsional,
saran, dan himbauan agar masyarakat tidak merasa diperintah atau
ditekan demi tercapainya tujuan pamflet.
105
DAFTAR PUSTAKA
Alwi, Hasan. 1992. Modalitas dalam Bahasa Indonesia. Yogyakarta:Kanisius.
Andryanto, Sugeng Febry. 2014. “Analisis Praanggapan pada PercakapanTayangan “Sketsa” di Trans Tv”. Jurnal Penelitian Bahasa, SastraIndonesia dan Pengajarannya. Volume 2 Nomor 3. Surakarta:Universitas Sebelas Maret.
Baisu, Laode. 2015. “Praanggapan Tindak Tutur dalam Persidangan diKantor Pengadilan Negeri Kota Palu”. e-Jurnal Bahasantodea,Volume 3 Nomor 2, hlm 129-143. Palu: Universitas Tadulako.
Baskoro, Suryo B. R. 2014. “Pragmatik dan Wacana Korupsi”. JurnalHumaniora. Vol. 26, No. 1. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Cummings, Louise. 2007. Pragmatik Sebuah Perspektif Multidisipliner.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Chaer, Abdul. 1994. Linguistik Umum. Jakarta: Rineka Cipta.
Cook, Walter A. 1971. Introduction to Tegmememics Analysis. Newyork:Holt, Rinehart, and Winston.
Djajasudarma, T. Fatimah. 1993. Metode Linguistik: Ancangan MetodePenelitian dan Kajian. Bandung: PT Eresco.
_________. 1999. Semantik 2, Pemahaman Ilmu Makna. Bandung: PT.Refika Aditama.
_________. 2012. Wacana dan Pragmatik. Bandung: Refika Aditama.
Felicia. 2013. “Analisis Makna Kanyouku yang Menggunakan Kanji Koshidalam Kodansha’s Dictionary of Basic Japanesse Idioms”. JurnalLingua Cultura. Vol. 7, No. 1. Jakarta: Binus University.
Gusnawaty. 2011. “Perilaku Kesantunan dalam Bahasa Bugis AnalisisSosiopragmatik”. Disertasi. Makassar: Pascasarjana UniversitasHasanuddin.
Hafid, Abdul. 2015. “Ragam Bahasa Iklan Pada Media Cetak”. Tesis tidakditerbitkan. Makassar: Program Pascasarjana UniversitasHasanuddin
106
Halliday, M.A.K. dan Hasan R. 1994. Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-Aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial. TerjemahanBarori T. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Halliday, M.A.K. 1985. An Introduction to Functional Grammar. London:Edwards Arnold.
Hasan, Mu’ammar. 2012. “Makna Leksikal dan Kontekstual dalam BentukMakian Bahasa Jawa Ngoko”. Jurnal Lingustika Akademika. Vol.1, No. 2. Bali: Universitas Udayana.
Hurford, R. James, dkk. 2008. Semantich: a Cousrsebook. Cambridge:Cambridge Univerity Press.
Kridalaksana, Harimurti. 1993. Kamus Linguistik. Jakarta Gramedia.
Kusumawati, Tri Indah. 2014. “Kata dan Pilihan Kata”. Jurnal Al-Irsyad.Vol. 4, No. 1. Sumatera Utara: IAIN Sumatera Utara.
Leech, Geoffrey N. 2011. Prinsip-Prinsip Pragmatik. Jakarta: UniversitasIndonesia-Pres.
Levinson, S.C. 1983. Pragmatics. London: Cambridge University Press.
Mahsun. 2012. Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, danTekniknya (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
Mulyana. 2005. Kajian Wacana: Teori, Metode dan Aplikasi Prinsip-PrinsipAnalisis Wacana. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Nababan, P.W.J. 1987. Ilmu Pragmatik: Teori dan Penerapannya. Jakarta:Depdikbud.
Nadar, F.X. 2009. Pragmatik dan Penelitian Pragmatik. Yogyakarta: GrahaIlmu.
Pelawi, Bena Yusuf. 2009. “Aspek Semantik dan Pragmatik dalamTerjemahan”. Jurnal Lingua Cultura. Vol. 3, No. 2. Jakarta: BinusUniversity.
Poerwadarminta, 2011. KBBI Cetakan ke Delapan Belas Edisi IV. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
Program Pascasarjana. 2015. Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi.Edisi 4. Makasaar: Universitas Hasanuddin.
107
Rahardi, Kunjana. 2002. Pragmatik: Kesantunan Imperatif BahasaIndonesia. Jakarta: Erlangga..
Rahyono, F.X. 2011. Studi Makna. Jakarta: Penaku.
Ramlan. M. 2005. Ilmu Bahasa Indonesia; Sintaksis. Yogyakarta. CVKaryono.
Rusminto, Nurlaksana Eko. 2012. Analisis Wacana Sebuah Kajian Teoritisdan Praktis. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
Rohmadi, Muhammad. 2014. “Kajian Pragmatik Guru dan Siswa dalamPembelajaran Bahasa Indonesia”. Jurnal Poedogogia. Vol. 17,No.1. Surakarta: FKIP Univeersitas Sebelas Maret.
Samsuri. 1987. Analisis Bahasa. Jakarta: Erlangga.
Santoso, Anang. 2008. “Jejak Halliday dalam Linguistik Kritis dan AnalisisWacana Kritis”. Jurnal Bahasa dan Seni. Tahun ke-36, No. 1.Padang: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang.
Siahaan, Lusmiati. 2015. “Pemakaian Praanggapan pada TuturanWisatawan Asing dalam Berinteraksi Dengan Penduduk SetempatDi Ubud Bali”. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Slametrianto. 2009. Aplikasi Desain Grafis untuk Periklanan. Yogyakarta:Andi.
Subagyo, P. Ari. 2010. “Pragmatik Kritis: Paduan Pragmatik denganAnalisis Wacana Kritis”. Jurnal Masyarakat Linguistik Indonesia(MLI). Tahun ke-28 No. 2. Jakarta: Unika Atma Jaya.
Sudaryat, Yayat. 2004. Struktur Makna Prinsip-Prinsip Studi Semantik.Bandung: Raksa Cipta.
_________. 2009. Makna dan Wacana. Bandung: Yrama Widya.
Sudaryanto. 1986. Metode Linguistik - Bagian Pertama : Ke ArahMemahami Metode Linguistik. Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press.
Sutopo, H.B. 2002. Metodeologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNSPress.
108
_________. 1993. Metode dan Aneka Teknik Analisi Bahasa. Yogyakarta:Duta Wacana University Prees.
Trask, R.L. 1999. Key Concepts in Language and Linguistics. London:Routledge.
Ullmann, Stephen. 2014. Pengartar Pragmatik. Penerjemah: Sumarsono.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Verhaar, J.W.M. 2010. Asas-Asas Linguistik Umum. Yogyakarta: GadjahMada University Press
Wijana, I Dewa Putu. 1996. Dasar-Dasar Pragmatik. Yogyakarta: AndiOffset.
Winarni, Lilis Wahyuni. 2015. “analisis praanggapan pernyataan humordalam stand up comedy indonesia”. Tesis tidak diterbitkan.Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas PendidikanIndonesia.
Yule, George. 2014. Pragmatik. Penerjemah Indah Fajar Wahyuni.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
___________. 1996. Analisis Wacana. Penerjemah Sutikno. Jakarta:Gramedia.
Data 1
(a) Habis senam pungut sampah.
(b) Keren...!!!
Lokasi : Pantai Marina
Partisipan : LSM Kamelia, dan masyrakat pengunjung
Pantai Marina
Waktu : 2017
Konteks : pamflet dipegang oleh anak sekolah dasar
(SD) pada saat senam pagi.
Data 2
(a)Wakatobi bersih tanpa sampah.
(b)Stop buang sampah ke laut.
Lokasi : Pantai Marina
Partisipan : LSM Kamelia, dan masyrakat pengunjung
Pantai Marina
Waktu : 2017
Konteks : pamflet dipegang oleh anak sekolah dasar
(SD) pada saat senam pagi
Data 3
Sampahmu milikmu!!
Lokasi : Pantai Marina
Partisipan : LSM Kamelia, dan masyrakat pengunjung
Pantai Marina
Waktu : 2017
Konteks : pamflet dipegang oleh anak perempuan dan
bapaknya pada saat senam pagi.
Data 4
Nelayan yang gemar membom dan membius ikan adalah musuh alam.
Lokasi : Pantai Marina
Partisipan : LSM Kamelia, dan masyrakat pengunjung
Pantai Marina
Waktu : 2017
Konteks : pamflet dipegang oleh seorang pria dewasa
pada saat senam pagi
Data 5
(a) Tak kenal maka tak sayang.
(b) Lihatlah lebih dalam.
(c) Lestarikan kekayaan lautmu.
Lokasi : perkampungan Bajo
Partisipan : LSM, dan masyarakat Bajo
Waktu : 2017
Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi di
pelabuhan nelayan. Pelabuhan selalu ramai didatangi
oleh masyarakat bajo yang menunggu kerabat mereka
pulang dari melaut. Selain itu banyak juga kalangan
penjual ikan yang menunggu nelayan dan hendak
membeli hasil tangkapannya. Isi pamflet disertai gambar
ikan-ikan dan terumbu karang.
Data 6
(a) Jaga dan cintai terumbu karang.
(b) Mereka ada agar kami ada.
Lokasi : perkampugan Bajo
Partisipan : LSM, dan masyarakat Bajo
Waktu : 2017
Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi di pos
informasi wisata komplek pendidikan dekat pintu
gerbang perkampungan bajo. Isi pamflet disertai gambar
ikan-ikan dan terumbu karang.
Data 7
Jaga terumbu karang untuk anak cucu kita.
Lokasi : Pasar Sore Wanci
Partisipan : Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan
Pengunjung pasar
Waktu : 2017
Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi dekat
penjualan ikan
Data 8
(a) Terimakasih atas partisipasinya dalam melestarikan
terumbu karang.
(b) Terumbu karang sehat, ikan berlimpah, masyarakat
sejahtera.
Lokasi : Pasar Pagi Wanci
Partisipan : Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Coremap II, dan pengunjung pasar
Waktu : 2017
Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi
Data 9
(a) Sayangi karang.
(b) Jangan injak karang.
Lokasi : Pasar Pagi Wanci
Partisipan : Coremap II, dan pengunjung pasar
Waktu : 2017
Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi
Data 10
(a) Ala sagaa, heboka ako tey langento.
(b) Ambil sebagian, simpan untuk hari esok
Lokasi : Pasar Sore, Wanci
Partisipan : Coremap II, WWF, RARE, dan pengunjung
pasar
Waktu : 2017
Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi.
Pamflet dilengkapi dengan gambar ikan-ikan.
Data 11
(a) Sadarkah anda?
(b) Betapa berharganya mereka jika sudah dikelola
(c) Kenali potensi dan peluang investasi pulau-pulau kecil
indonesia
Lokasi : Pasar Sore, Wanci
Partisipan : Coremap II, WWF, RARE, dan pengunjung
pasar
Waktu : 2017
Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi dekat
penjualan ikan
Data 12
(a) Tahukah kamu laut indonesia sangat kaya?
(b) Ikan melimpah nelayan sejahtera.
Lokasi : Pasar sentral,Mandati
Partisipan : Coremap II, WWF, RARE, dan pengunjung
pasar
Waktu : 2017
Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi dekat
terminal
Data 13
Selamatkan laut indonesia dari sampah karena laut masa depan bangsa.
Lokasi : Perkampungan Bajo
Partisipan : Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan
masyrakat Bajo
Waktu : 2017
Konteks : hari peduli sampah nasional 2017
Data 14
(a) Save Turtle.
(b) Lestarikan penyu dan jangan jadikan mereka buruan.
Lokasi : Pantai Marina
Partisipan : LSM Kamelia, dan masyrakat pengunjung
Pantai Marina
Waktu : 2017
Konteks : pamflet dipegang oleh anak laki-laki dan
ibunya pada saat senam pagi.
Data 15
(a)Save me guys.
(b)Ikan hiu adalah teman bukan untuk dimakan.
Lokasi : Pantai Marina
Partisipan : LSM Kamelia, dan masyrakat pengunjung
Pantai Marina
Waktu : 2017
Konteks : pamflet dipegang oleh anak sekolah dasar
(SD) pada saat senam pagi.
Data 16
Terapkan budaya buang sampah pada tempatnya.
Lokasi : Mandati
Partisipan : LSM Kamelia, Dinas Kesehatan Kabupaten
Wakatobi, Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dan
masyrakat pengunjung pasar
Waktu : 2017
Konteks : Terminal pasar sentral Mandati.
Data 17
Bumi saja aku jaga, apalagi kamu.
Lokasi : Lapangan Merdeka
Partisipan : LSM Kamelia, dan masyrakat peserta pawai
Waktu : 2017
Konteks : hari bumi 2017. Pamflet dipegang oleh
perempuan dewasa.
Data 18
Mari selamatkan sumberdaya perikanan kita.
Lokasi : Perkampungan Bajo
Partisipan : Kementerian kelautan dan perikanan, dan
masyarakat bajo
Waktu : 2017
Konteks : pamflet dipajang pada pusat informasi di pos
kamling
.
Data 19
(a) Kalian boleh tangkap kami, tapi kalian harus lestarikan
rumah kami.
(b) Bagaimana??
(c) Deal??
Lokasi : Pasar Pagi Wanci
Partisipan : Kementerian kelautan dan perikanan,
Lingkungan Hidup, LSM Coremap II, dan masyrakat
pengunjung pasar
Waktu : 2017
Konteks : pamflet dipajang pada pos informasi pasar