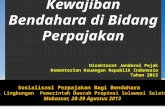GAMBARAN PENGHAYATAN PERAN IBU DALAM SOSIALISASI IDENTITAS GENDER ANAK PEREMPUAN KELUARGA TIONGHOA
Transcript of GAMBARAN PENGHAYATAN PERAN IBU DALAM SOSIALISASI IDENTITAS GENDER ANAK PEREMPUAN KELUARGA TIONGHOA
i
GAMBARAN PENGHAYATAN PERAN IBU DALAM
SOSIALISASI IDENTITAS GENDER ANAK PEREMPUAN
KELUARGA TIONGHOA
Oleh
Anastasia Setyaning A.S.
2008-070-048
Dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Fakultas Psikologi
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya di Jakarta
pada tanggal..................................
Menyetujui, Pembimbing Skripsi
Dr. Nani I.R. Nurrachman, Psikolog.
Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Katolik Atma Jaya
Dr. phil. Juliana Murniati
Fakultas Psikologi
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta
Juli 2012
ii
ABSTRAK
Anastasia Setyaning A.S. 2008-070-048
Gambaran Penghayatan Peran Ibu dalam Sosialisasi Identitas Gender Anak
Perempuan Keluarga Tionghoa
ix + 112 halaman, 11 tabel, 2 gambar
Bibliografi 49 (1978-2012)
Relasi paling awal yang dialami seorang manusia adalah hubungan dengan
ibunya (Chodorow, 1978). Melalui relasi dengan ibu, self anak terbentuk dan anak
memahami self-nya berdasarkan hubungan dirinya dengan ibu. Diri seorang ibu
sebagai perempuan adalah self-in relation (Chodorow, 1978). Maka secara
bersamaan ibu pun membentuk self dan pemahaman dirinya tentang self melalui
interaksi dengan anak-nya. Pada anak perempuan yang memiliki kesamaan
ketubuhan dengan ibu, perkembangan dirinya dibangun melalui connectedness
dengan ibu. Di pihak ibu, kesamaan ketubuhan ini menyebabkan hadirnya
kembali seluruh pengalaman hidup ibu sebagai perempuan. Berbeda dari
psikologi arus utama yang memandang self terbentuk melalui otonomi dan
keterpisahan dari pengasuh utama, psikologi perempuan melihat diri perempuan
terbentuk melalui relasi ibu dan anak perempuan.
Pada keluarga Tionghoa yang patriarkis, ibu dan anak perempuan
memiliki pengalaman dibedakan yang sama. Sebab perempuan dipandang sebagai
warga kelas dua dalam budaya Tionghoa (Meij, 2009). Pada konteks kehidupan
masyarakat Indonesia, perempuan Tionghoa bahkan mengalami dibedakan dua
kali. Pertama, dibedakan karena gendernya, kedua, dibedakan karena etnisnya.
Sementara perempuan keluarga Tionghoa tetap bertahan hidup dan menjalani
kehidupannya sehari-hari dari generasi ke genarasi. Setiap hari dalam keseharian
hidupnya, mereka mengalami pembedaan ini dari lingkungan sosial. Maka dalam
kondisi seperti ini, peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran peran ibu dalam
sosialisasi identitas gender anak perempuan di keluarga Tionghoa. Sebab dengan
mengetahui peran ibu, dapat diketahui gambaran pembentukan identitas gender
yang dilakukan ibu kepada anak perempuan yang notabene memiliki kesamaan
ketubuhan dengan ibu. Selain itu, dengan mengetahui pengalaman ibu sebagai
anak dan perempuan, dapat ditelusuri bagaimana seorang ibu menginternalisasi,
merefleksikan, menginterpretasikan dan menghayati hidupnya. Pada akhirnya
keseluruhan proses ini mempengaruhi Ibu saat menjalani perannya.
Untuk memperoleh gambaran penghayatan peran ibu ini, dilakukan
penelitian dengan metode kualitatif, yaitu melalui wawancara mendalam (in-depth
interview) pada dua pasang ibu dan anak perempuan keluarga Tionghoa yang
berdomisili di Jakarta. Subjek dikontrol melalui pembatasan usia anak perempuan
yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu dewasa muda (early adulthood).
Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa ibu menghayati perannya sebagai
agen perubahan bagi anak perempuannya sehingga anak perempuan tidak lagi
mengalami pembedaan karena gender seperti yang dialami ibunya.
iii
KATA PENGANTAR
Penelitian ini berawal dari kepedulian dan keingintahuan pribadi yang tak
dapat dilepaskan dari stimulus orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitar
peneliti. Maka pertama-tama peneliti ingin berterima kasih pada (Alm.) Emak
Maria Gouw Giok Eng (1917-2005) yang memberikan paparan (exposure)
pertama bagaimana menjalani hidup sebagai perempuan peranakan Tionghoa-
Indonesia. Serta fasilitasi pembelajaran luar biasa yang telah diberikan oleh kedua
orang tua peneliti sampai hari ini, Stephanus Djoko Satriyo dan Anselma Wiwiek
Widiarti.
Pada saat menjalani proses penelitian, peneliti mengalami banyak proses
pembelajaran melalui kendala literatur, subyektivitas pribadi dan faktor individual
peneliti. Maka peneliti juga ingin berterima kasih pada orang-orang yang telah
berkontribusi secara akademis maupun moril dan emosional terhadap peneliti
sepanjang penulisan skripsi ini, yaitu :
1. Dr. Nani I.R.Nurrachman, Psikolog., pembimbing akademik sekaligus
pembimbing skripsi peneliti. Terima kasih untuk relasi menghidupkan
yang menstimulus rasa ingin tahu dan pembelajaran akan dinamika
dan kearifan hidup, dimulai dari diri sendiri.
2. Dra. Prilyani Pranaya. Terima kasih telah memberikan bantuan
literatur dan koneksi untuk menghubungi Ibu Myra Sidharta dan Prof.
Dr. Melani Budianta. Untuk Ibu Myra Sidharta dan Prof. Dr. Melani
Budianta, terima kasih untuk bantuan literatur dan pemikiran pada
tahap awal penelitian ini.
3. Dr. Sherley-Lim dari Gender Studies, University of California.
Pertemuan penuh kesan di Ubud Writers & Readers Festival pada
bulan Oktober 2011, dilanjutkan pertemuan pada Biennale Sastra
Komunitas Salihara, yang memberikan kontribusi pemikiran dan
bantuan literatur.
4. Aquino Hayunta, S. Sos. Terima kasih telah memfasilitasi perkenalan
dengan Diyah Wara, M.Si, ketua komunitas pemuda Ikatan Indonesia-
Tionghoa (INTI). Tempat peneliti berdiskusi menjelang pengambilan
data responden.
5. Perpustakaan Kajian Wanita Universitas Indonesia, Salemba yang
menyediakan berbagai literatur yang dibutuhkan peneliti untuk
menyusun kerangka penelitian.
6. Anggita Hotna Panjaitan yang memfasilitasi perkenalan dengan Farid
Hanggawan, S.H.. Terima kasih untuk kesedian berdiskusi dan bantuan
literatur tentang filsuf perempuan.
7. Ibu dan anak perempuan yang menjadi subjek penelitian ini. Mereka
menjadi pionir usaha dan kerinduan untuk memotret kehidupan ibu-
anak perempuan keluarga Tionghoa masa kini.
8. Teman-teman, karyawan dan dosen Fakultas Psikologi Unika Atma
Jaya yang memfasilitasi pembelajaran dan dukungan melalui interaksi
sehari-hari. Terutama untuk :
iv
- Sebastian Partogi, S.Psi, Raina Paramitha, S. Psi, Rebeka Pinaima,
S.Psi, Pithe Lim, S.Psi., dan Okki Sutanto, S.Psi.
- Grace Maria Sininta, S.Psi, Amelia Hartono, S.Psi, Kenny Ahldrin,
S.Psi, Anastasia Primasari, S. Psi, Cendy Sanada, Silvyana,
Griselda Jane, Marius Dion dan Almira Rahma.
- Sylvia Dewi Suryaganda dan Nadya Regina Pryana.
- Inez Kristanti, Tesar Gusmawan, Arnold Lukito, Gabriela Angie,
Edwin Nathaniel.
9. Stephani Fitria Winda Satriyo dan Maria Yohanna Widianti Satriyo.
Kedua adik peneliti, sparing partner tumbuh berkembang sebagai
perempuan, yang memberi ruang pemakluman dan pembelajaran
selama menyelesaikan skripsi. Keluarga besar Akong Lim Bun Jie
yang telah memberikan bantuan dan dukungan.
10. Bontor Humala, S.T.. Terima kasih untuk kesegaran, ketenangan,
keteguhan dan semangat yang peneliti peroleh melalui interaksi
bersama.
Hidup adalah proses bertanya. Jawaban hanyalah persinggahan dinamis
yang bisa berubah seiring dengan berkembangnya pemahaman kita (Dee, 2011).
Pada titik persinggahan saat ini, penelitian ini menjadi kulminasi pencarian dan
pertanyaan saya. Terima kasih yang dalam untuk transendensi yang
mengejewantah dalam Allah, Cinta dan alam semesta yang memungkinkan diri
saya untuk menjadikan ini ada.
Exploration is really the essence of the human spirit (Frank Borman).
Who looks outside, dreams. Who looks inside, awaken (Carl Jung).
Jakarta, Juli 2012
Peneliti
v
DAFTAR ISI
Halaman Pengesahan......................................................................................... i
Abstrak Skripsi.................................................................................................. ii
Kata Pengantar.................................................................................................. iii
Daftar Isi........................................................................................................... iv
Daftar Tabel...................................................................................................... v
Daftar Gambar.............................................. ................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN................................................................................
I.A. Latar Belakang Masalah.................................................................
I.B. Perumusan Masalah........................................................................
I.C. Tujuan Penelitian............................................................................
I.D. Manfaat Penelitian.........................................................................
I.D.1. Manfaat Teoritis........................................................................
I.D.2. Manfaat Praktis.........................................................................
I.E. Sistematika Penulisan.....................................................................
1
1
10
10
10
10
10
11
BAB II LANDASAN TEORI..........................................................................
II.A. Psikologi Perempuan Berbeda dengan Psikologi Laki-Laki......
II.B. Psikologi Perkembangan Perempuan..........................................
II.B.1. Perkembangan Diri Sendiri.................................................
II.B.1.1. Teori Gender................................................................
II.B.1.1.1. Perspektif social-learning-theory.........................
II.B.1.1.2. Perspektif psikodinamika....................................
II.B.1.1.3. Perspektif developmental constructive...............
II.B.1.2. Sosialisasi Identitas Gender..................................
II.B.2 Reproduksi Peran Ibu.........................................................
II.B.2.1. Peran Ibu....................................................................
II.B.2.2. Interaksi Ibu dan Anak Perempuan............................
II.B.3. Perempuan dalam Budaya Tionghoa di Indonesia............
II.B.3.1. Terbentuknya Identitas Diri pada Perempuan di
Keluarga Tionghoa.......................................................
II.C. Kerangka Penelitian....................................................................
13
13
13
13
13
16
17
18
20
21
21
23
29
33
40
BAB III METODE PENELITIAN....................................................................
III.A. Jenis Penelitian......................................................................
III.B. Instrumen Penelitian..............................................................
III.C. Subjek Penelitian.....................................................................
III.C.1. Karakteristik Subjek.......................................................
III. D. Prosedur Penelitian...............................................................
III.D.1. Tahap Persiapan............................................................
III.D.2. Cara Memperoleh Subjek..............................................
III.D..3. Tahap Pelaksanaan.......................................................
III.E. Metode Analisis Data...............................................................
41
42
45
45
45
46
46
47
48
50
BAB IV HASIL PENELITIAN.......................................................................
IV.1. Deskripsi Latar Belakang Subyek.............................................
IV.2.1. Hasil Temuan Data Penelitian..........................................
IV.2.1.1. Latar Belakang Ibu Subyek Pertama........................
53
53
53
53
vi
IV.2.1.2. Latar Belakang Anak Perempuan Subyek
Pertama....................................................................
IV.2.1.3. Pengalaman Ibu sebagai Anak Perempuan
Keluarga Tionghoa.................................................
IV.2.1.4. Kesadaran akan Adanya Perubahan Nilai-nilai
yang Disosialisasikan..............................................
IV.2.1.5. Sosialisasi Identitas Gender pada Anak Perempuan
IV.2.1.6. Pengalaman Ibu dan Anak Perempuan dengan
Identitas Ke-Tionghoa-an.......................................
IV.2.2. Subyek Kedua.................................................................
IV.2.2.1. Latar Belakang Ibu Subyek Kedua........................
IV.2.2.2. Latar Belakang Anak Perempuan Subyek Kedua...
IV.2.2.3. Pengalaman Ibu sebagai Anak Perempuan
Keluarga Tionghoa................................................
IV.2.2.4. Kesadaran akan Adanya Perubahan Nilai-nilai
yang Disosialisasikan.............................................
IV.2.2.5. Sosialisasi Identitas Gender pada Anak Perempuan
IV.2.2.6. Pengalaman Ibu dan Anak Perempuan dengan
Identitas Ke-Tionghoa-an........................................
IV.3. Analisis Antar Subyek...........................................................
IV.3.1. Latar Belakang Kehidupan Ibu....................................
IV.3.2. Pengalaman Ibu sebagai Anak Perempuan di
Keluarga Tionghoa......................................................
IV.3.3. Kesadaran akan Adanya Perubahan Nilai-nilai
yang Disosialisasikan...................................................
IV.3.4. Sosialisasi Identitas Gender pada Anak Perempuan.....
IV.3.5. Pengalaman Ibu dan Anak Perempuan dengan
Identitas Ke-Tionghoa-an............................................
IV.4. Dinamika Penghayatan Peran Ibu dalam Sosialisasi
Identitas Gender Anak Perempuan Keluarga Tionghoa.......
56
58
60
62
64
67
67
71
72
75
75
79
82
85
85
89
91
95
98
100
BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN DISKUSI...........................................
V.A. Kesimpulan................................................................................
V.B. Diskusi........................................................................................
V.C. Saran...........................................................................................
V.C.1. Saran Metodologis.............................................................
V.C.1.1. Pemilihan Subjek Penelitian........................................
V.C.2. Saran Praktis.....................................................................
108
108
109
112
112
112
Daftar Pustaka
Lampiran
vii
DAFTAR TABEL
Tabel IV.A.1. Deskripsi Latar Belakang Subyek..................................................52
Tabel IV.C.1.1. Perbandingan Latar Belakang Kehidupan Ibu.............................85
Tabel IV.C.1.2. Perbandingan Usia Menikah Ibu..................................................88
Tabel IV.C.1.3. Perbandingan Pendidikan Akhir Ibu............................................88
Tabel IV.C.2.1. Perbandingan Pengalaman Ibu sebagai Anak Perempuan Keluarga
Tionghoa......................................................................................89
Tabel IV.C.3.1. Perbandingan Perubahan Nilai-nilai yang Disosialisasikan........92
Tabel IV.C.3.2. Perbandingan Perubahan Nilai-nilai yang Disosialisasikan pada
Anak Perempuan..........................................................................93
Tabel IV.C.4.1. Perbandingan Sosialisasi Identitas Gender dari Ibu.....................95
Tabel IV.C.4.2. Perbandingan Sosialisasi Identitas Gender pada Anak
Perempuan....................................................................................97
Tabel IV.C.5.1. Perbandingan Pengalaman Ibu dengan Identitas Ke-Tionghoa-an
................................................................................................................................98
Tabel IV.C.5.2. Perbandingan Pengalaman Anak Perempuan dengan Identitas Ke-
Tionghoa-an...........................................................................................................98
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.A.1. Dinamika relasi ibu dan anak perempuan dalam sosialisasi..........7
Gambar II.B.1. Dinamika Teori Penelitian...........................................................41
ix
DAFTAR LAMPIRAN
Surat Pernyataan Kesediaan Subjek
Panduan Pertanyaan
Tabel Analisa Perbandingan Ibu-Anak Perempuan
1
BAB I
PENDAHULUAN
I.A. Latar Belakang Masalah
Know Thy Self~Socrates (469-399 SM)
Manusia adalah makhluk yang senantiasa mempertanyakan dirinya, yang
selalu “menjadi” (becoming). Perjalanan manusia dalam mempertanyakan dan
mengenal dirinya dapat dilihat dari perjalanan sejarah manusia (Wibowo, 2009).
Di dalam ilmu psikologi, perjalanan sejarah seorang manusia dari konsepsi
sampai kematian dipelajari pada Psikologi Perkembangan. Pembelajaran
mengenai life-span development berisi informasi mengenai siapa diri kita,
mengapa kita menjadi seperti saat ini dan bagaimana seluruh pengalaman hidup
mempengaruhi masa depan kita (Santrock, 2008). Proses pembelajaran ini dapat
memunculkan isu dan pertanyaan terkait perkembangan diri manusia.
Pada diri peneliti, pertanyaan muncul dari hasil refleksi diri terhadap
pengalaman hidup selama dua puluh tahun sebagai perempuan dikaitkan dengan
materi Psikologi Perkembangan. Peneliti menyadari adanya perbedaan identitas
feminin yang diperoleh dalam interaksi di keluarga inti dengan ekspektasi
identitas feminin yang ada di lingkungan masyarakat.
Kedua orang tua peneliti sampai saat ini tidak pernah mendidik ketiga anak
perempuannya menggunakan batasan gender. Kedua orang tua terutama ibu,
mendidik anak perempuan dengan paradigma sebagai manusia ciptaan Tuhan
2
seluruh potensi diri dan talenta perlu dikembangkan dengan maksimal
(komunikasi pribadi, 9 April 2011). Segala usaha untuk memaksimalkan potensi
dan kemampuan diri dikaitkan dengan kebergunaan bagi sesama, lingkungan
sekitar, bangsa dan tanah air. Sementara di lingkungan masyarakat ada batasan
bagi anak perempuan untuk mengaktualisasikan diri karena identitas gendernya
(“Nasib Kartini”, 2012). Anak perempuan terikat oleh nilai-nilai kultural yang
membatasi pilihan dan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri.
Melalui interaksi dengan teman sebaya sejak tingkat sekolah dasar hingga hari
ini yang dilegitimasi melalui komunikasi pribadi (12 April 2011), peneliti
memperoleh informasi bahwa pemahaman dan keyakinan yang dimiliki oleh
teman-teman perempuan mengenai bagaimana harus berpikir dan bertingkah laku
sebagai perempuan diperoleh dari ibu mereka. Seorang teman, Bunga (bukan
nama sebenarnya) memperoleh pengajaran dari ibunya bahwa seorang perempuan
semandiri apapun tetap harus mengurus dan memikirkan keluarganya. Sedangkan
teman lain, sebut saja Citra memperoleh pengajaran dari ibunya bahwa sebagai
perempuan harus bisa menjadi orang yang mandiri dan bisa berdiri di atas kaki
sendiri sehingga kehidupannya terutama dari segi keuangan tidak tergantung pada
suami. Teman lain bernama Sari diajari ibunya sejak kecil untuk bangun pagi dan
rajin membereskan kamar sebab ia seorang anak perempuan.
Teman lain, Mita, diminta ibunya untuk selalu menjaga kebersihan kuku
tangan dan kakinya sebab nanti mertua perempuan akan menilai menantunya dari
kebersihan kuku tangan dan kaki. Sementara Kasih, tidak diperbolehkan ibunya
menggaruk kulit tangannya jika digigit nyamuk. Sebab ibunya tidak ingin kulit
3
anaknya lecet dan menjadi jelek karena digaruk akibat gatal. Menurut ibunya,
salah satu aspek kecantikan perempuan adalah kebersihan dan kehalusan kulit.
Ada juga Jane yang sering diributkan oleh ibunya untuk menjaga berat badan.
Tapi jika ibunya melihat Jane makan terlalu sedikit, ia pun akan meributkannya
juga.
Melalui wawancara lebih lanjut, diketahui pengajaran para ibu kepada anak
perempuannya ini diperoleh dari pengalaman ibu sebagai perempuan. Pengalaman
yang berbeda-beda dari para ibu memunculkan pengasuhan yang berbeda pada
anak perempuan. Pengalaman ibu di budaya patriarki diwariskan kepada anak
perempuan yang memiliki kesamaan ketubuhan dengan ibu. Maka, Ibu akan
merasa tegang dan sangat khawatir bila anak perempuannya gagal memenuhi
tuntutan peran yang diharapkan oleh budaya patriarki (Poerwandari, 2011).
Seorang sosiolog dan psikoanalis feminis, Nancy Chodorow (1978)
berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki mengalami perkembangan dan
sosialisasi berbeda karena pengalaman hidup mereka terkait dengan jenis kelamin.
Maka untuk memahami perkembangan manusia secara penuh hanya bisa dicapai
dengan memahami pengalaman laki-laki dan pengalaman perempuan secara
spesifik (Surrey, 1985).
Pengalaman ibu dan anak perempuan yang hidup di budaya patriarkis seperti
yang dipaparkan di atas tidak pernah dibahas dalam psikologi arus utama (Miller,
1986). Padahal relasi ibu dan anak perempuan mempengaruhi dasar dari struktur
utama self mereka (Surrey, 1985). Menurut Chodorow (1978) self dibentuk dari
4
relasi paling awal yang dialami manusia, yaitu hubungan dengan ibu. Selama
sembilan bulan di awal masa kehidupannya anak menjadi bagian (a part) dari
ketubuhan ibunya. Seiring dengan pertumbuhkembangan anak di dalam
kandungan ini eksistensi ibu mulai muncul, demikian telaah Nurrachman (2011)
terhadap Freud & Chodorow.
Secara spesifik, ibu dan anak perempuan memiliki ikatan yang lebih khusus
dibandingkan ibu dengan anak laki-laki (Chodorow, 1978). Dari segi biologis ibu
dan anak perempuan memiliki aspek ketubuhan yang sama sehingga identitas
feminin anak perempuan berkembang dalam konteks keterikatan dengan ibunya,
demikian telaah Nurrachman (2011) terhadap Chodorow. Identitas feminin anak
perempuan dipengaruhi oleh sosialisasi yang dialami dalam hidupnya. Salah satu
agen sosialisasi yang berperan bagi anak perempuan adalah ibunya sendiri. Hal-
hal yang ditransmisikan ibu terhadap anak perempuan di dalam proses sosialisasi
tersebut amat dipengaruhi oleh bagaimana ibu menginternalisasikan nilai budaya
dan masyarakat di mana ia berada (Chodorow, 1978).
Menariknya, jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat peran
menjadi ibu telah dipersiapkan dan disosialisasikan kepada perempuan sejak ia
masih kanak-kanak (Hidajadi, 2010). Chodorow (1978) bahkan memaparkan
bahwa kemampuan untuk menjadi ibu “direproduksi” dari ibu kepada anak
perempuannya melalui struktur di dalam hubungan keluarga yang menciptakan
landasan psikologis untuk menjadi ibu (mothering). Misalnya saja, sejak kecil
anak perempuan diberikan mainan yang berkisar pada boneka-bonekaan dan alat-
alat memasak yang menstimulus munculnya perilaku mengasuh dan merawat
5
serta munculnya berbagai peraturan dan larangan agar perempuan tetap
mempunyai sikap yang diangggap pantas bagi seorang perempuan (Hidajadi,
2010). Terlihat bahwa secara psikologis perempuan dipersiapkan untuk menjadi
ibu melalui perkembangan situasi di mana ia bertumbuh kembang bersama
dengan perempuan yang mengasuhnya (Chodorow, 1978).
Ketika seorang perempuan menjadi ibu yang membesarkan anak perempuan, ia
akan bercermin pada dirinya sendiri dengan harapan bahwa anak perempuannya
memperoleh tempat di masyarakat yang patriarki ini (Hidajadi, 2010). Walaupun
demikian, pemahaman dan penghayatan konsep perempuan akan dipersepsi
berbeda-beda oleh perempuan itu sendiri. Perbedaan biopsikologis dan
pengalaman hidup yang melekat pada perempuan membawa konsekuensi pada
cara perempuan mempersepsi dan menghayati dunia realitas serta melakukan
aktivitas di dalamnya (Nurrachman, 2011). Akhirnya, muncul sosok Ibu sebagai
suatu peran dengan dua sisi identitas, yaitu sisi personal berupa konsep diri dan
sisi sosial di mana peran ibu dipengaruhi oleh mitos-mitos dan harapan
masyarakat. Hal ini merupakan telaah Nani Nurrachman terhadap Rubin (2011).
Bagi anak perempuan, figur ibu tampil sangat kuat sebagai stimulus dalam
kognisi anak, yaitu secara ketubuhan, cara berpikir, konsep, maupun dalam nilai
simbolik (Nurrachman, 2011). Di dalam interaksi ibu dan anak perempuan terjadi
proses sosialisasi gender (Corell, 2007) yang meliputi proses kognitif yang
mempengaruhi bagaimana ibu dan anak perempuan menerima, menginterpretasi
dan merespon dunia sosial mereka
6
Maka, pembentukan gender bukan hanya terjadi secara alamiah tetapi
dipengaruhi oleh sosialisasi ibu di dalam keluarga yang merupakan sistem sosial
pertama bagi anak (Gerungan, 2004). Konsep gender sendiri berada di tiga tahap
analisis, yaitu individual, interaksional, dan struktural (Risman, 1998).
Kajian terhadap berbagai penelitian mengenai gender dengan paradigma
psikologi sosial, memberikan pemahaman bahwa gender bukanlah sebuah atribut
menetap melainkan sebuah proses interaksi yang terus menerus terjadi (West &
Zimmerman, 1987). Gender juga dilihat sebagai suatu sistem yang multi-level
(Shelley, 2007). Dengan demikian, gender di tataran individu merupakan suatu
identitas yang diperoleh melalui interaksi sehari-hari di masyarakat berdasarkan
ekspektasi gender yang ada.
Terkait dengan interaksi, munculnya interaksi yang tidak seimbang secara
berulang antara laki-laki dan perempuan memunculkan keyakinan kultural
mengenai perbedaan gender (Eagly & Steffen, 1984 dan Ridgeway dalam Shelley,
2007). Keyakinan kultural mengenai perbedaan gender ini dibawa dan
ditransmisikan oleh ibu dalam interaksinya dengan anak perempuan. Selain
pengaruh keyakinan kultural, cohort kelahiran dan generasi di mana ibu tumbuh
dan berkembang juga akan mempengaruhi bagaimana ia menunjukkan perannya
sebagai ibu dan mentransmisikan sosialisasi gender kepada anak perempuannya
(Fischer, 1991).
Menurut Fischer (1991) ikatan di antara ibu dan anak perempuan, terutama
pada anak perempuan dewasa menjadikan peran ibu (mothering) sebagai hal
7
utama di dalam hidup mereka. Secara langsung maupun tidak langsung, hubungan
ini menjadi penghubung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini dapat
dilihat dalam dinamika sebagai berikut.
Bio Psiko Sosio
Ibu
Agama lingkungan
Bio Psiko Sosio
Media
Anak Perempuan
Budaya
Tradisi
Ibu
Bio Psiko Sosio
Lingkungan
Agama
Anak
Bio Psiko Sosial Media
Gambar 1.A.1. Dinamika relasi ibu dan anak perempuan dalam sosialisasi
Pembelajaran, Penghayatan &
Kesadaran
Sosialisasi
8
Seperti yang telah dipaparkan di atas, perlu ditengarai bagaimana proses
sosialisasi peran gender dilakukan oleh ibu sebagai pengasuh pertama dan utama
anak perempuan. Hal ini perlu dilakukan untuk semakin memahami diri
perempuan sebagai manusia dengan keunikan dan karakteristik yang khas.
Sosialisasi peran gender yang diperoleh dari interaksi antara ibu dengan anak
perempuannya akan memberikan gambaran yang lebih kontekstual dan
komprehensif mengenai dinamika perempuan sebagai manusia.
Menurut Fischer (1991) ada beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan
dalam melakukan penelitian antara ibu dan anak perempuan. Variabel tersebut
antara lain, cohort generasi ibu maupun anak perempuan seperti yang sudah
dipaparkan di atas, kelas sosial dan kultur. Woehrer dalam Fischer (1991)
memaparkan adanya perbedaan ekspektasi keluarga dan perilaku terkait dengan
etnisitas.
Indonesia sebagai negara multikultural memiliki keunikan dan kekhasan etnis
yang beragam. Setiap etnis memiliki karakteristiknya masing-masing. Interaksi
dan persinggungan antar etnis pun juga memunculkan dinamika dan karakteristik
yang unik. Di dalam penelitian terhadap peran ibu dalam sosialisasi gender
terhadap anak perempuan ini, penelitian akan difokuskan kepada satu etnis yaitu
etnis Tionghoa. Pemilihan ini berdasarkan kenyataan adanya pelekatan stereotipe
dua kali pada perempuan beretnis Tionghoa (Meij, 2009). Pertama pada
identitasnya sebagai perempuan, kemudian ditambahkan lagi dengan penghayatan
psikologis yang ditimbulkan dari internalisasi etnis Tionghoa di dalam dirinya.
9
Pelekatan stereotipe dua kali pada perempuan beretnis Tionghoa menyebabkan
munculnya perasaan didiskriminasi. Merasa berbeda dan didiskriminasi
mempengaruhi pemaknaan self pada perempuan Tionghoa seperti yang
dipaparkan Mely G. Tan (2008) dari hasil wawancara terhadap perempuan berusia
31 tahun yang berdomisili di Bali, "We are Indonesians of Chinese origin, but we
also know we are not Balinese. We are different from the Balinese, but then we
are not real Chinese either". Pada generasi muda Tionghoa di Indonesia juga
muncul kebingungan sebab mereka lebih melihat diri sebagai orang Indonesia
ketimbang Tionghoa. Mereka menyadari darah Tionghoa mereka walaupun
memiliki pengetahuan yang minim tentang tradisi dan budaya Tionghoa. Namun
mereka merasa diperlakukan berbeda dari mayoritas etnis lain yang ada di
Indonesia. Kondisi ini juga dirasakan oleh dua belas orang mahasiswa Fakultas
Psikologi Unika Atma Jaya dalam komunikasi pribadi (22 November 2011).
Kedekatan peneliti dengan budaya Tionghoa dikarenakan memiliki ibu yang
ber-etnis Tionghoa diharapkan dapat meningkatkan sensitivitas yang diperlukan
untuk memahami permasalahan di dalam penelitian ini. Selain itu melalui kajian
literatur ditemukan bahwa penelitian mengenai Tionghoa di Indonesia amatlah
minim, padahal mereka berkontribusi terhadap tujuh puluh persen sektor ekonomi
swasta Negara Indonesia (Tan, 2008). Maka, penelitian semacam ini diharapkan
dapat membantu masyarakat memahami perilaku manusia dari etnis yang telah
berasimilasi dan bersinggungan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pengakuan
akan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an negara Indonesia perlu diwujudkan dalam
penelitian seperti ini.
10
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran penghayatan peran ibu
dalam sosialisasi identitas gender anak perempuan keluarga Tionghoa. Jika tujuan
penelitian ini tercapai maka ilmu psikologi yang bertujuan untuk memahami
manusia (dirinya sendiri) berdasarkan interaksi antar manusia dapat semakin
terwujud dan dikembangkan. Terlebih tujuan dari psikologi perempuan secara
khusus, yaitu untuk memahami realitas kehidupan perempuan yang bersumber
dari pengalaman hidup individu perempuan. Secara bersamaan terjadi proses
refleksi atas pengalaman serta interaksi yang reflektif untuk menghasilkan temuan
serta pengetahuan ilmiah yang berspektif perempuan, serta lebih realistis dan
humanis (Nurrachman, 2011).
Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan
dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian akan dilakukan
dengan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) yang akan dilakukan
pada ibu dan anak perempuan usia dewasa muda yang berada dalam satu ikatan
keluarga kandung dan tinggal bersama di satu rumah.
I.B. Perumusan Masalah
“Bagaimana gambaran penghayatan peran Ibu dalam sosialisasi identitas gender
anak perempuan keluarga Tionghoa?
11
I.C. Tujuan Penulisan
Penulisan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai peran ibu
dalam sosialisasi identitas gender anak perempuan. Dengan demikian tercipta
usaha memahami realitas kehidupan perempuan yang bersumber dari pengalaman
hidup individu perempuan.
I.D. Manfaat Penelitian
I.D.1. Manfaat Teoritis
Perolehan gambaran mengenai peran ibu dalam sosialisasi identitas gender
anak perempuan diharapkan memberi referensi dalam perkembangan psikologi
perempuan di Indonesia. Terutama mengenai pemahaman yang lebih mendalam
mengenai dinamika peran ibu dalam proses sosialisasi para calon ibu untuk
generasi selanjutnya, yaitu para anak perempuan.
1.D.2. Manfaat Praktis
1. Memberikan pemahaman kepada psikolog, aktivis dan konselor mengenai
peran ibu dalam sosialisasi identitas gender anak perempuan
2. Memberikan kesadaran pada ibu dan anak perempuan yang terlibat dalam
siklus ibu-anak secara berkelanjutan dalam memahami dinamika relasi dan peran
masing-masing di dalam relasi tersebut.
A. Sistematika Penulisan
Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Pada Bab 1
12
diberikan pemaparan mengenai perlunya melakukan penelitian mengenai
gambaran peran ibu dalam sosialisasi identitas gender anak perempuan keluarga
Tionghoa. Bab II berisi tinjauan kepustakaan terkait dengan penelitian ini
mengenai paradigma psikologi perempuan, reproduksi peran ibu dan relasi ibu
dan anak perempuan di keluarga Tionghoa Indonesia. Bab III berisi metodologi
dan prosedur penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini. Bab IV berisi
hasil penelitian berupa data yang didapatkan. Dalam bab tersebut akan dibahas
gambaran umum hasil penelitian maupun hasil penelitian secara detail serta
perbandingan antara satu data dengan data yang lain. Bab V berisi hasil penelitian
beserta kesimpulan, diskusi dan saran yang terkait dengan hasil penelitian ini.
13
BAB II
LANDASAN TEORI
II.A. Psikologi Perempuan Berbeda dengan Psikologi Laki-laki
Psikologi arus utama yang berkembang dewasa ini seringkali
menyamaratakan pengalaman hidup laki-laki dan perempuan, terlebih jika hal ini
dikuantifikasikan ke dalam angka. Laki-laki dan perempuan hanya menjadi
simbol jenis kelamin yang tak bermakna apa-apa pada hasil-hasil penelitian yang
dipublikasikan. Padahal jika ingin memahami manusia secara utuh, diperlukan
usaha untuk menyelami kehidupan perempuan maupun laki-laki secara holistik
pula (Nurrachman, 2011). Psikologi yang berkembang di Barat menurut
Nurrachman (2011) cenderung mengarah ke sifat andosentris di mana konsep-
konsep yang terbentuk memerlukan usaha rekonstruksi agar sesuai dengan
pemaknaan yang lebih tepat bagi perempuan.
Psikologi perempuan berbeda dari psikologi laki-laki, sebab perlu disadari
bahwa perbedaan pengalaman hidup perempuan tidak bisa dilepaskan dari faktor
biologis dirinya yang dikenai persepsi sosial-budaya lingkungannya. Perjalanan
perempuan untuk memahami dirinya masih berada dalam batasan-batasan objektif
ketubuhan dan lingkungan sosial budaya. Hal ini sangat jauh berbeda dari
pengalaman dan batasan yang diberikan kepada laki-laki di dalam masyarakat.
Tentu saja hal ini juga akan mempengaruhi bagaimana laki-laki mempersepsikan
diri dan dunia sosialnya. Pada perempuan, salah satu batasan yang dialaminya
adalah melalui perannya sebagai ibu (Nurrachman, 2011). Peran sebagai ibu yang
14
telah disosialisasikan pada anak perempuan sejak usia dini dan kemudian
dialaminya secara langsung, memunculkan diri (self) perempuan yang senantiasa
berada dalam bentuk ‘diri-dalam-relasi’ yang saling tarik menarik dengan diri
sebagai ‘aku’ yang mandiri (Nurrachman, 2011).
Melalui perspektif psikologi perempuan, diharapkan perempuan dapat
dipandang dan dipahami sebagai manusia dengan segala dinamika psike yang
dialaminya. Kecenderungan yang ada selama ini tinjauan mengenai perempuan
cenderung dilihat sebagai ‘yang lain’ oleh konstruksi sosial budaya masyarakat.
Oleh karena itu, tinjauan menggunakan faktor biospikososiokultural yang
berperan di dalam kehidupan perempuan diharapkan mampu memberikan konteks
untuk memahami perempuan sebagai subjek (Nurrachman, 2011) sekaligus untuk
memperoleh gambaran bagaimana perempuan “menyatakan diri” melalui
penghayatan dirinya.
Peneliti mengambil posisi sebagai perempuan dengan menggunakan
perspektif psikologi perempuan untuk melihat diri ibu dan anak perempuan dalam
keluarga Tionghoa secara holistik dan reflektif melalui penuturan mereka akan
pengalaman hidup sebagai perempuan. Perkembangan psikologi perempuan
secara teoritis akan dipaparkan di bawah ini.
II.B. Psikologi Perkembangan Perempuan
II.B.1. Perkembangan Diri Sendiri
II.B.1.1. Teori Gender
15
One is born female or male, but one is socialized to be feminine or masculine
(Cobb, 2000)
Gender merupakan salah satu bagian penting di dalam pembentukan konsep
diri (self concept) sebab gender memainkan peran penting dalam usaha manusia
untuk mendefinisikan dan menjalani dunia mereka (Sroufe, 1996). Salah satu
sarana penting untuk memahami diri adalah melalui pemahaman mengenai
gendernya. Proses identifikasi gender ini dimulai dari umur dua tahun (Cobb,
2000) di mana anak dapat mengidentifikasikan dirinya sebagai anak laki-laki atau
anak perempuan. Proses ini disebut sebagai labelisasi gender (gender labeling).
Sebagian besar anak-anak usia dini, kesulitan membedakan jenis kelamin (sex)
dengan gender. Jika jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis seperti sistem
reproduksi (Cobb, 2000), maka gender lebih menekankan pada pemahaman dan
pembentukan kultural mengenai apa yang disebut sebagai maskulin dan feminin.
Perbedaan gender ditentukan secara sosial melalui proses sosialisasi.
Pada rentang usia antara tiga sampai lima tahun, anak mulai
mengembangkan pemahaman mengenai gender constancy (Cobb, 2000).
Pemahaman ini sejalan dengan sex constancy di mana anak memahami bahwa
jenis kelamin merupakan suatu hal yang permanen dan tidak akan berubah
semata-mata berdasarkan cara seseorang berpakaian. Kemudian secara bertahap
muncul stereotipe gender (gender stereotyping) yang mengajarkan pada anak
mengenai tipe pakaian yang ia kenakan, mainan seperti apa yang cocok untuk
dimainkan serta membayangkan pekerjaan seperti apa yang dijalaninya sebagai
16
orang dewasa. Hal-hal seperti ini berkontribusi pada perkembangan identitas
gender anak sesuai dengan pengalaman mereka sebagai laki-laki maupun
perempuan (Cobb, 2000).
Perkembangan stereotipe gender pada anak terjadi melalui berbagai cara.
Secara umum ada tiga pandangan mengenai terbentuknya stereotipe gender, yaitu
perspektif social-learning-theory, perspektif psikodinamika dan perspektif
developmental constructive (Cobb, 2000).
II.B.1.1.1. Perspektif social-learning-theory
Social-learning-theory menekankan pentingnya peran kekuatan eksternal
dalam membentuk perilaku yang sesuai dengan gender di mana perilaku-perilaku
tersebut merupakan hasil dari suatu pembelajaran. Orang tua memiliki peran
penting dalam proses pembelajaran, baik sebagai model yang diimitasi oleh anak
maupun sebagai pemeran aktif dalam membentuk perilaku anak-anak mereka.
Secara sadar pada umumnya orang tua merasa tidak membeda-bedakan perilaku
dalam bersikap terhadap anak laki-laki dan anak perempuannya. Namun pada
sebuah penelitian yang mengobservasi perilaku ibu (Will, Self & Datan dalam
Cobb, 2000) ditemukan bahwa ibu akan memberikan mainan yang berbeda saat
berinteraksi dengan balita yang dianggap sebagai laki-laki dan perempuan.
Para ibu yang terlibat dalam penelitian ini berkata pada para peneliti
bahwa mereka tidak akan bersikap berbeda kepada anak laki-laki dan perempuan
mereka. Pada masa ini pula perilaku sesuai dengan jenis kelamin (sex-typed
behavior) mulai muncul di usia dua tahun (Sroufe, 1996). Walaupun pada
17
awalnya anak memiliki pemahaman yan terbatas mengenai perilaku sesuai gender,
namun pada usia tiga sampai empat tahun anak akan semakin mengetahui objek
dan aktivitas yang sesuai dengan gender serta semakin memunculkan perilaku
sesuai dengan jenis kelamin (sex-typed behavior).
II.B.1.1.2. Perspektif psikodinamika
Perspektif psikodinamika berawal dari pandangan aliran psikoanalisa
mengenai proses internalisasi mengenai perilaku melalui proses identifikasi.
Melalui identifikasi pada orang tua berjenis kelamin yang sama dengan dirinyaa
(same-sex parent), anak menginternalisasikan semua perilaku dan sikap dari orang
tuanya. Keinginan yang kuat untuk menjadi sama seperti orang tua dari gender
yang sama menyebabkan anak akan mengadopsi perilaku, sikap dan nilai-nilai
yang dimiliki oleh orang tuanya (Soufre, 1996). Proses pengadopsian ini
melibatkan elemen kognitif karena membutuhkan kemampuan anak untuk
mengenali persamaan gender antara dirinya dengan salah satu dari kedua orang
tuanya, lalu membuat abstraksi yang membantunya menggolongkan orangtuanya
sebagai laki-laki atau perempuan.
Chodorow (1978) melihat bahwa anak perempuan mendefinisikan
femininitasnya melalui persamaan yang dimiliki dengan ibunya. Teori Chodorow
berdasar pada asumsi Freudian di mana laki-laki dan perempuan memiliki
hubungan yang paling kuat dalam relasi dengan ibunya. Anak laki-laki
memisahkan diri dari ibunya dalam usaha mengidentifikasi diri, sedangkan anak
perempuan menekankan pada kesamaan antara dirinya dengan ibunya. Proses
18
identifikasi ini menjadi dasar dari perbedaan gender dan seksualitas pada masa
dewasa di kemudian hari. Perempuan akan cenderung mendefinisikan dirinya
dalam keterhubungan dengan orang lain, melihat orang lain dari kesamaan yang
dimilikinya serta memiliki kapasitas yang lebih besar untuk merasakan perasaan
orang lain (Soufre, 1996).
II.B.1.1.3. Perspektif developmental constructive
Pendekatan ini mengasumsikan anak-anak mengkonstruksikan identitas
seksual mereka dengan meniru perilaku orang lain yang sesuai gender secara
selektif, baik perilaku gender yang dilakukan oleh orang tuanya maupun oleh
orang lain. Persepsi selektif dan bukan identifikasi dianggap sebagai proses yang
bertanggung jawab pada perkembangan perilaku gender yang diharapkan (Marin
& Helverson, Bem dalam Cobb, 2000).
Proses persepsi yang selektif ini dibimbing oleh skema gender. Skema
gender merupakan suatu struktur kognitif yang mengarahkan proses pemerolehan
informasi mengenai dirinya sendiri. Skema gender bekerja sesuai dengan tingkat
kesiapan menerima informasi tertentu berdasarkan konsistensi dari suatu skema
gender seseorang . Melalui sebuah penelitian yang dilakukan Carol Martin dan
Halverson serta Bruce Carter dan Gary Levy dalam Cobb (2000) pada anak-anak
di taman kanak-kanak, ditemukan bahwa anak-anak dengan skema gender yang
lebih kuat dan solid memiliki kesulitan mengingat gambar dari suatu aktivitas
yang inkonsisten dengan peran jenis kelamin (sex roles) dan lebih mungkin
19
melakukan kesalahan pada jenis kelamin karakter yang sesuai dengan aktivitas
pada gambar yang mereka ingat kembali.
Sandra Bem dalam Cobb (2000) berpendapat bahwa gender memiliki
cognitive primacy melebihi kategori sosial lainnya karena pentingnya gender di
dalam suatu masyarakat. Perkembangan anak-anak menggunakan skema gender
dalam memproses informasi mengenai diri mereka dan anak-anak lain sedikit
banyak bergantung pada bagaimana gender dikembangkan dalam proses
sosialisasi di masyarakat. Selain itu, perkembangan konsep mengenai peran
gender juga dipengaruhi oleh tingkat kematangan kognitif serta berbagai
pengalaman yang diceritakan maupun diperlihatkan sebagai perilaku yang sesuai
untuk anak laki-laki dan anak perempuan.
Penelitian ini akan menggunakan perspektif social-learning theory dan
perspektif psikodinamika. Kedua perspektif ini digunakan untuk lebih memahami
permasalahan penelitian secara lebih komprehensif dan holistik. Sesuai dengan
teori Chodorow (1978) bahwa pembentukan identitas antara ibu dan anak
perempuan terbentuk dari interaksi di dalam relasi mereka. Ibu menjadi seorang
ibu dan berperilaku seperti ibu karena adanya kehadiran dari anak perempuan dan
anak perempuan berperilaku seperti perempuan karena adanya kehadiran ibu.
Kehadiran ibu dan anak perempuan memunculkan interaksi mutualisme
yang saling memunculkan identitas mereka masing-masing sebagai perempuan.
Di dalam diri mereka masing-masing terjadi pula perkembangan psikodinamika
sebagai individu yang menghayati diri di dalam relasi. Pemaknaan terhadap relasi
20
dengan ibu dan penghayatan terhadap diri pribadi (self) atas seluruh peristiwa
hidup yang dialami menjadi suatu proses tersendiri di dalam diri mereka masing-
masing. Dengan demikian, perspektis social learning theory dan psikodinamika
diperlukan dan relevan untuk memahami penelitian ini.
II.B.1.2. Sosialisasi Identitas Gender
Setelah mengetahui bagaimana gender dipahami anak sejak usia dini, perlu
dipahami pula bagaimana sosialisasi gender terjadi di dalam keluarga sebagai
lingkup sosial yang terkecil. Psikologi sosial tentang gender mempelajari
bagaimana gender dibentuk dan dipengaruhi melalui interaksi sosial (Correl,
2007). Selain dipengaruhi oleh interaksi sosial, sosialisasi gender juga melibatkan
proses kognitif (Correl, 2007). Gender mempengaruhi bagaimana kita menerima,
menginterpretasi dan memberikan respon pada dunia sosial di sekitar kita.
Sosialisasi gender juga melibatkan mekanisme bagaimana interaksi tersebut
didefinisikan dalam rangka transmisi makna mengenai gender. Oleh karena itu,
gender bukanlah semata-mata trait dari seorang individu saja melainkan prinsip
yang terorganisir di dalam semua sistem sosial, termasuk keluarga, pekerjaan,
sekolah, ekonomi, sistem hukum dan interaksi sehari-hari (Correl. 2007).
Para ilmuwan mengkonseptualisasikan gender sebagai institusi di dalam
tiga tingkatan analisis, yaitu tingkat individual, interaksional dan struktural
(Risman dalam Correl, 2007). Tingkat individual merujuk pada trait yang stabil
dari laki-laki dan perempuan yang muncul selama kurun waktu tertentu.
Perbedaan di tingkat individual dipercaya berakar dari perbedaan biologis atau
21
pada sosialisasi anak-anak di usia dini. Pada tingkat interaksional, dikaji
bagaimana perilaku sosial difasilitasi atau dibatasi oleh ekspektasi dari orang-
orang sesuai dengan trait mengenai laki-laki dan perempuan yang mereka miliki
di masyarakat mereka. Sedangkan pada tingkat struktural dikaji bagaimana pola di
tingkat makro, seperti posisi yang diharapkan orang di masyarakat atau imbalan
yang diperoleh dari posisi tersebut mengarahkan pada perbedaan-perbedaan
perilaku atau pengalaman yang dialami perempuan dan laki-laki. Perkembangan
penelitian akhir-akhir ini di dalam psikologi sosial mengenai gender sebagian
besar berfokus pada tingkat interaksional untuk melihat bagaimana ekspektasi
gender membentuk perilaku (Correl, 2007).
Penelitian ini akan menggunakan tingkatan analisis individual dan
interaksional. Tingkatan analisis individual diperlukan untuk memahami
karakteristik individu ibu dan anak perempuan, sedangkan tingkatan interaksional
diperlukan untuk memahami bagaimana interaksi antara anak maupun ibu di
dalam relasi mereka maupun dengan lingkungan sosial di sekitarnya membentuk
pola perilaku gender tertentu berdasarkan pandangan yang dimiliki oleh keluarga
Tionghoa mengenai perempuan sebagai ibu maupun anak.
II.2.2. Reproduksi Peran Ibu
II.2.2.1. Peran Ibu
Chodorow (1978) mengatakan Ibu memiliki peran penting sebagai
pengasuh pertama dan utama bagi anak sehingga ia menjadi sumber identifikasi
(identification) bagi anak. Ibu berperan sebagai pendidik pertama anak, konselor
22
dan menjadi sumber vital bagi dukungan emosional dan keibuan (Kraemer, 2006).
Melalui diri ibu sebagian besar manusia pertama kali belajar mengenal cinta,
kekecewaan, kekuatan dan kelembutann (Rich dalam Hirsch, 1981). Relasi ibu
dengan anak menstimulus pertumbuhkembangan anak sejak masa awal
pertumbuhkembangannya. Pada anak perempuan proses identifikasi terhadap
ibunya berlanjut sepanjang hidupnya, sementara anak laki-laki sejak masa awal
kehidupannya berusaha memisahkan diri dan menjadi berbeda dari ibunya.
Boyd dalam Bickmore (1995) mengatakan bahwa ibu menjadi role model
utama dan pendidik dalam nilai-nilai budaya (cultural values). Pengalaman ibu
bertahan hidup di dunia yang patriarki menjadi landasan baginya untuk
mentransmisikan nilai dan aturan terkait keperempuanan pada anak
perempuannya sehingga anak perempuannya juga dapat bertahan (survive) di
dunia ini (Gilbert & Webster dalam Bickmore, 1995). Pada ibu di kelompok
masyarakat (society) yang memberikan pengasuhan eksklusif serta menjadikan
hubungan ini paling bermakna bagi anaknya maka anak mampu
menumbuhkembangkan sense of self bertitik tolak pada hubungan dengan ibunya
(Chodorow, 1978). Cara ibu mengasuh melalui interaksi dengan anak menjadi
landasan bagi anak di kemudian harinya untuk mengembangkan hubungan intim
dan romantik berdasarkan pengalaman bersama ibu. Anak mendambakan
kebersatuan dalam hubungan bersama dengan orang lain seperti pengalamannya
bersama ibunya ketika ia masih kecil (Chodorow, 1978). Ketika anak menjadi ibu
di saat dewasa, ia akan mengulang kembali pengalaman ia bersama ibunya dahulu
kala. Maka pengalaman menjadi ibu dan ekspektasi yang dimiliki ibu dipengaruhi
23
oleh sejarah pengalaman di masa kecilnya, relasinya terdahulu dan relasinya saat
ini (Chodorow, 1978).
Ibu menjadi simbol ketergantungan, regresi, pasivitas dan minimnya
adaptasi terhadap realita. Menurut Chodorow (1978) dengan berbalik dari diri ibu
seseorang dapat menjadi wanita dan laki-laki dewasa. Sayangnya ibu seringkali
merasa bahwa dirinya memiliki kebersatuan (oneness) dengan anak. Anak juga
dipandangnya sebagai perluasan dari dirinya (extension of the self). Ibu perlu
mengetahui kapan saat yang tepat untuk membiarkan anaknya berdiferensiasi dari
dirinya dan mulai memisahkan diri. Pada situasi seperti ini ibu menciptakan
ambivalensi pada anak.
Di satu sisi ia harus memberikan kesempatan pada anaknya untuk
memisahkan diri dan berbeda dari dirinya tapi di sisi lain ia juga masih harus
membimbing anaknya hingga mencapai tahap pertumbuhkembangan yang
maksimal. Ibu menjadi figur yang sangat kuat tampil sebagai stimulus dalam
kognisi anak, khususnya pada anak perempuan secara ketubuhan, cara berpikir,
konsep, maupun dalam nilai simbolik (Nurrachman, 2011).
II.B.2.2. Interaksi Ibu dan Anak Perempuan
Ibu tercipta karena adanya kehadiran anak, anak pun terlahir karena
adanya ibu. Maka eksistensi Ibu dan anak sama-sama muncul di saat yang
bersamaan melalui interaksi mereka. Interaksi ibu dan anak memiliki kekhasan
sebab selama sembilan bulan pertama anak menjadi bagian (a part) dari
ketubuhan ibu di dalam kandungannya, demikian telaah Nurrachman (2011)
24
terhadap Freud & Chodorow. Lalu setelah anak lahir, ia muncul dalam sosok
tubuh yang berbeda dan terpisah dari ibu secara ketubuhan. Maka melalui proses
pertumbuhkembangan selanjutnya, anak akan belajar membentuk dan
mengembangkan diri pribadi yang secara fisik dan psikologis ‘terpisah’ (apart)
dari ibunya.
Proses ini bukanlah suatu hal yang mudah bagi ibu, sebab secara sadar
maupun tidak sadar ibu sering menganggap ada kemenyatuan (oneness) antara
dirinya dengan anak dan anak merupakan perluasan dari diri ibu (extension of the
self) (Chodorow, 1978). Anak perempuan yang memiliki aspek ketubuhan yang
sama dengan ibu akan semakin merasa sulit memisahkan diri dari ibu dalam
proses identifikasi yang dimulai sejak usia empat tahun ini (Nurrachman, 2011).
Memahami hubungan di antara mereka menjadi hal yang penting sebab ikatan
antara anak perempuan dengan ibunya merupakan relasi yang kompleks dan
saling ketergantungan. Ikatan ini seringkali menghambat anak perempuan untuk
membangun identitas dirinya sendiri (Bickmore, 1995). Dari sisi ibu, ia
mengembangkan hubungan dan identitas yang lebih kuat dengan anak
perempuannya sebagai perluasan dari dirinya sendiri. Menurut Carol Boyd dalam
Lucy Fisher pada Journal of Mother-Daughter Relationship (1995) sepanjang
hidupnya anak perempuan akan bergumul untuk memisahkan diri dari ibunya.
Berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri sebagai perempuan, ibu
mendidik anak perempuan tergantung pada orang lain. Menurut Nice dalam
Bickmore (1995) ibu mendidik anak perempuannya untuk memenuhi kebutuhan
laki-laki dan menekan kebutuhannya sendiri. Perempuan dididik menjadi atraktif
25
dan perhatian, tidak terlihat lebih menonjol secara intelektual dibandingkan laki
laki dan selalu mencari penerimaan dari orang lain. Ikatan antara ibu dan anak
perempuan merupakan ikatan pertama dan paling mendasar dalam kehidupan
perempuan yang saling membentuk satu sama lain. Interaksi di dalam hubungan
ini seringkali menjadi kompleks, namun perempuan dewasa muda memiliki
kebutuhan untuk memahami ibunya sehingga dapat memahami dirinya sendiri
(Notar & McDaniel dalam Bickmore, 1995).
Pada interaksi yang kompleks ini masing-masing pihak memiliki
pemaknaan tersendiri terhadap interaksi mereka sehingga mereka pun memiliki
persepsi masing-masing yang berbeda di dalam relasi ini (Kraemer, 2006). Teori
psikoanalisa memandang interaksi ibu dan anak perempuan secara tidak sadar
menginternalisasikan nilai-nilai pengasuhan ibu (maternal values) dan pemaknaan
terhadap nilai dan perilaku yang dimunculkan ibu pada diri anak perempuan
(Boyd, 1989). Sementara teori social learning melihat bahwa anak perempuan
belajar menjadi ibu dan menjadi seperti ibunya melalui konsistensi dan penguatan
perilaku (reinforcement) yang diberikan ibu ketika ia meniru perilaku ibunya
(Weitzman dalam Boyd ,1984).
Ikatan antara ibu dan anak perempuan merupakan expresi yang yang jelas
dan detail tentang kedekatan (intimacy) dan keberjarakkan (distance), hasrat
(passion) dan kekerasan (violance). Hubungan yang paling pribadi sekaligus
paling universal di saat yang bersamaan (Boyd, 1989). Pada hubungan ini pula
anak perempuan memunculkan ambivalensi terhadap ibu sebagai musuh sekaligus
objek dari keinginan (object of desire). Hubungan yang ambivalen ini
26
mendominasi keseluruhan hidup perempuan, terutama dalam relasinya dengan
suami atau orang yang dicinta.
Sampai masa dewasa, ibu masih menjadi inner object yang penting bagi
anak perempuan dalam telaah object-relation psychologist. Dalam relasi ibu
dengan anak perempuannya, sebenarnya ibu juga sedang mengurai relasinya yang
belum terselesaikan dengan ibunya sendiri (Boyd, 1989). Interaksi antara ibu dan
anak perempuan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan
berkelanjutan. Menurut Jung dalam Boyd (1989), di dalam diri setiap ibu
bersemayam anak perempuan di dalam dirinya dan setiap anak perempuan
memiliki diri ibunya. Setiap perempuan mengalami proses putar balik ke belakang
terhadap ibunya dan ke depan menghadapi anak perempuannya.
Nurrachman (2011) dalam telaah terhadap teori Chodorow mengatakan
bahwa penghayatan keibuan merupakan sublimasi psikologis. Bagaimana
perempuan mengkonstruksi dan menghayati perannya sebagai ibu tidak terlepas
dari figur ibunya sendiri. Ibu menjadi aktor utama dalam dasar pembentukan
pribadi anak perempuan. Proses diferensiasi antara anak perempuan dengan
ibunya, akan menjadi landasan bagi anak perempuan untuk menjadi perempuan
yang berbeda dari ibunya (Nurrrachman, 2011).
Menjadi ibu merupakan proses yang dipelajari dan ditanamkan terus
menerus ke dalam diri perempuan. Dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari
bahwa peran menjadi ibu telah dipersiapkan sejak seorang perempuan masih
kanak-kanak (Hidajadi, 2010). Hal ini terlihat dari mainan yang diberikan pada
27
anak perempuan yang berkisar pada boneka-bonekaan dan alat-alat memasak serta
berbagai peraturan dan larangan yang dikenakan pada perempuan untuk tetap
mempunyai sikap yang dianggap pantas bagi seorang perempuan (Hidajadi,
2010). Jadi, anak perempuan sudah disosialisasikan sejak dini untuk menjadi
seorang perempuan dan bahkan seorang ibu di masa-masa mendatang.
Ketika seorang perempuan menjadi ibu yang harus membesarkan anak
perempuannya, ia akan bercermin pada dirinya sendiri dengan harapan bahwa
anak perempuannya memperoleh tempat di masyarakat yang patriarki ini
(Hidajadi, 2010). Pemahaman dan penghayatan konsep perempuan akan
dipersepsi berbeda-beda oleh perempuan itu sendiri. Perbedaan biopsikologis dan
pengalaman hidup yang melekat pada perempuan membawa konsekuensi pada
cara perempuan mempersepsi dan menghayati dunia realitas serta melakukan
aktivitas di dalamnya (Nurrachman, 2011).
Peran gender ini akan terbawa pada dinamika interpersonal antara ibu
dengan anak perempuannya. Ini mencakup bagaimana ibu dan anak perempuan
sebagai sesama perempuan menghadapi mitos dan stereotipi masyarakat dan
sejauh mana ibu dan anak perempuannya saling mengakui satu sama lain sebagai
indiividu (Nurrachman, 2011) dan mengembangkan identitas diri sebagai diri
pribadi yang sejati (real-self) berhadapan dengan diri perempuan yang diidealkan
masyarakat (idealized self). Sebagai contoh, Titi Sjuman-seorang aktris, musikus
dan seniman- dalam wawancara dengan majalah Femina (“4 Cinta”, 2011)
mengatakan untuk urusan cita-cita anak perempuannya bernama Miyake yang
28
berusia lima tahun, ia berkaca dari pengalamannya dahulu sebagai anak. Dulu,
orang tuanya tidak mengizinkan Titi menjadi musikus.
Padahal menurutnya setiap anak berhak memiliki kebebasan memilih cita-
cita. Maka ketika saat ini ia menjadi ibu bersama dengan suami yang berprofesi
sebagai musikus, ia merasa wajib memperkenalkan pengetahuan dasar musik pada
Miyake. Tetapi kalau anaknya tidak tertarik, ia tidak akan dipaksa. Walaupun
sejauh ini, anaknya senang musik dan sudah pandai bernyanyi. Dari pengalaman
Titi, dapat dilihat bahwa pengembangan diri pribadi perempuan mengacu pada
refleksi atas sosialisasi dan pengalaman yang diperolehnya semasa ketika ia
menjadi anak perempuan sampai akhirnya ia sendiri menjadi ibu dan kini melihat
ibunya melalui kacamata perempuan dewasa (Nurrachman, 2011).
Dalam kaitan relasi ibu dengan anak perempuan terlihat adanya hubungan
yang berkesinambungan antara ibu dan anak perempuan dari generasi ke generasi
mengenai peran gender. Proses identifikasi ini merupakan hasil dari pengajaran
secara sadar mengenai perbedaan gender yang merupakan fenomena pembelajaran
yang akan terjadi secara terus menerus (Chodorrow, 1978). Pada umumnya anak
perempuan akan mengembangkan identitas yang sama dengan ibunya ketika
beranjak dewasa melalui pengalamannya berinteraksi bersama dengan ibunya.
Namun, pengalaman dan ekspektasi mengenai pengasuhan sebagai ibu juga
dipengaruhi oleh pengalaman pribadi masa kecilnya, serta relasi masa lalu dan
masa kini secara eksternal maupun internal dengan keluarga ini (Chodorow,
1978). Seluruh sejarah dan relasi yang dimilikinya ini membentuk suatu realitas
psikologis dirinya sendiri.
29
Melalui pembahasan pada teori gender, teori peran ibu dan interaksi antara
ibu dan anak perempuan terlihat bahwa proses identifikasi gender pada diri anak
perempuan tidak dapat dipisahkan dari interaksi dengan ibunya. Hal ini sesuai
dengan pendapat Chodorow (1978) bahwa diri perempuan merupakan diri dalam
relasi. Penelitian yang ingin melihat bagaimana proses identitas gender pada anak
perempuan terbentuk ini tidak dapat dilepaskan dari interaksi ibu dan anak
perempuan melalui pola asuh yang disosialisasikan sejak kecil.
Oleh karena itu perspektif psikodinamika dan teori social learning serta
tingkatan analisis individual dan interaksional akan menjadi kerangka berpikir
dalam penelitian ini. Untuk dapat melihat terjadinya social learning secara lebih
kontekstual maka digunakan konteks sosial budaya di dalam keluarga Tionghoa.
Konteks sosial budaya ini secara langsung maupun tidak langsung menjadi
paradigma dalam memandang perempuan, sebagai entitas gender maupun dalam
peran sebagai ibu dan anak perempuan serta interaksi di antara mereka.
II.2.3. Perempuan dalam budaya Tionghoa di Indonesia
Paradigma perempuan dalam budaya Tionghoa di Indonesia tidak dapat
dilepaskan dari konteks sosial, politik dan budaya yang melingkupinya.
Pengalaman warga keturunan Tionghoa selama lebih dari tiga puluh dua tahun di
masa Orde Baru yang dibedakan menyebabkan penghayatan ke-Indonesiaan yang
berbeda dibandingkan dengan etnis lainnya di Indonesia (Tan, 2008). Analisis
Mely G. Tan terhadap Wang dalam Tan (2008) mengungkapkan adanya
kompleksitas sekaligus pengalaman kontradiktif bagi warga keturunan Tionghoa
30
di Indonesia di masa Orde Baru yang masih terasa implikasinya hingga hari ini.
Secara de jure, mereka tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Mereka
pun tinggal di daerah demografis Wilayah Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
namun mereka merasa berbeda dari orang Indonesia lainnya maupun dari orang
Cina “yang sebenarnya” (Tan, 2008). Seorang perempuan peranakan dari
Denpasar, Bali pada wawancara dengan Mely G. Tan dalam Tan (2008) berkata
seperti ini “We are Indonesian of Chinese origin; but we also know we are not
Balinese, but then we are not real Chinese either”. Pengalaman perempuan
sebagai ‘yang lain’ (the other) seperti yang dipopulerkan oleh Simone de
Beauvoir dalam The Second Sex (1949) tampaknya terjadi berlapis dua kali pada
perempuan keturunan Tionghoa di Indonesia. Pada lapisan pertama, ia menjadi
‘yang lain’ karena jenis kelaminnya dan pada lapisan kedua ia menjadi ‘yang lain’
karena keetnisitasannya.
Perlu disadari bahwa kelompok Indonesia Tionghoa merupakan suatu
komunitas yang tinggi tingkat keanekaragamannya. Namun sampai saat ini
masyarakat awam cenderung memperlakukan mereka sebagai etnik yang bercorak
tunggal (monolitik) (Dawis, 2009). Menurut Tan (2008), terdapat kontinum yang
luas di dalam kelompok Indonesia Tionghoa. Di satu sisi kontinum terdapat orang
Indonesia Tionghoa yang sudah berakulturasi secara penuh dengan budaya dan
komunitas lokal dan di sisi konitum lain masih ada mereka yang secara kultural
berorientasi Cina. Sebagian besar di antara mereka adalah para pengusaha papan
atas Indonesia.
31
Di tengah-tengah dua kontinum ini mayoritas Indonesia Tionghoa
termasuk dalam kelompok peranakan, yaitu mereka yang secara kultural lebih
berorientasi Indonesia. Mereka menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lokal
di rumah, tidak lagi berbicara dalam bahasa Cina dan memiliki pengetahuan yang
minim tentang agama dan tradisi Tionghoa (Tan, 2008). Kelompok Indonesia
Tionghoa seperti ini dapat ditemui di kota-kota besar. Mereka tidak meragukan
kewarganegaraan Indonesia mereka namun masih menyadari darah Cina di dalam
diri mereka. Bagaimana mereka menghayati identitas diri mereka di tengah
keadaan de jure bahwa mereka warga negara Indonesia tapi secara de facto masih
mengalami perlakuan dan pandangan yang berbeda dipengaruhi kuat oleh ajaran
dan pendidikan di dalam keluarga (Dawis, 2009).
Pada penelitian untuk disertasinya, Dawis melakukan focus group
discussion (FGD) pada orang Indonesia Tionghoa yang berasal dari lima belas
kota berbeda di Indonesia. Ia menemukan keragaman jawaban dari para
respondennya terkait pandangan dan rasa suka (likeness) bergaul dengan orang
bukan Tionghoa, pribumi dan hubungan Tionghoa-pribumi. Menurut Dawis
(2009) kesadaran mereka sebagai orang Tionghoa juga berbeda-beda tergantung
pada tempat di mana mereka dibesarkan dan agama yang dipeluk. Di sisi lain, ada
nilai budaya, tradisi dan adat tertentu yang juga menyatukan orang Indonesia
Tionghoa. Salah satu faktor penting yang menyatukan respondennya adalah
keluarga mereka.
Di dalam keluarga Indonesia Tionghoa terdapat nilai-nilai Konfusius yang
masih dianut dan diwariskan kepada anak-cucu. Di antaranya adalah nilai
32
penghormatan terhadap orangtua dan leluhur. Menurut mereka penghormatan
pada leluhur memberikan mereka restu untuk mendapatkan keberhasilan (Dawis,
2009). Pada perempuan di keluarga Tionghoa, ajaran untuk hormat dan tunduk
pada orang tua lebih ditekankan dan disosialisasikan dibandingkan pada anak laki-
laki (Sidharta, 1987). Pada kelompok peranakan Indonesia yang modern seorang
anak perempuan atau istri yang baik mampu memenuhi permintaan dari keluarga
terutama dari figur maskulin yaitu ayah dan suami. Mereka juga dituntut untuk
menjalankan peran tradisional sebagai anak perempuan, istri dan ibu dengan baik
(Sidharta, 1987).
Budaya patriarki di dalam keluarga Tionghoa menempatkan perempuan
sebagai liyan (Meij, 2009). Tradisi dan budaya memberikan hak istimewa pada
laki-laki untuk membawa nama dan kehormatan keluarga padahal perempuan
berperan besar untuk meneruskan dan mempertahankan tradisi keluarga. Melalui
perempuan nilai-nilai dalam tradisi keluarga diinternalisasikan terutama pada anak
perempuan. Terkait dengan nilai penghormatan terhadap orang tua, keputusan-
keputusan hidup anak perempuan di keluarga Tionghoa masih sangat dipengaruhi
oleh orang tuanya. Misalnya saja dalam memilih jodoh. Orang tua tidak pernah
berkeberatan jika anak perempuannya berteman dengan pribumi tapi tidak
memperkenankan anaknya menikah dengan pribumi. Agama menjadi salah satu
faktor yang menghalangi anak perempuan di keluarga Tionghoa menikah dengan
pribumi (Dawis, 2009). Orang tua pun lebih mengharapkan anak perempuannya
menikah dengan laki-laki Tionghoa sehingga nilai budaya dan tradisi dapat
dipertahankan.
33
Paham Konfusius memunculkan paham mengenai wanita yang sempurna
bagi orang Tionghoa, yaitu mengikuti aturan kepatuhan dalam ajaran Konghucu.
Menurut Sidharta (1987) sebagai gadis yang belum menikah, ia harus patuh
kepada ayahnya dan kakak lelaki tertuanya; kalau sudah menikah ia harus patuh
pada suaminya; dan kalau ia janda patuh kepada anak lelakinya. Tuntutan
terhadap perempuan di keluarga Tionghoa amatlah tinggi namun mereka tidak
diberikan akses dan kesempatan yang sama dengan anak laki-laki untuk membuat
keputusan di dalam hidupnya (Meij, 2009). Pada konteks ini, identitas diri mereka
sebagai perempuan di keluarga Indonesia Tionghoa pun mengalami pergumulan
sekaligus pertumbuhkembangan. Padahal di saat yang bersamaan mereka masih
mempertanyakan pula identitas mereka sebagai bagian dari warga negara
Indonesia. Proses pergumulan identitas mereka pun menjadi berlapis-lapis
disertai pengalaman menjadi liyan atau the other berlapis ganda. Penelitian ini
ingin melihat proses pembentukan identitas perempuan di keluarga Tionghoa
terkait dengan konteks dan situasi yang mereka hadapi.
II.2. 3.1.Terbentuknya Identitas Diri pada Perempuan di Keluarga Tionghoa
Salah satu tokoh yang berjasa dalam perkembangan teori kepribadian
adalah Erik Erikson. Menurut Feist (2006) Erikson menekankan pengaruh dari
lingkungan dan masyarakat (society influence) dalam perkembangan kepribadian
seseorang. Menurutnya, kapasitas seorang anak yang baru lahir memang penting
terhadap perkembangan kepribadiannya. Namun, kemunculan ego paling banyak
dibentuk dari lingkungan (society). Bahkan menurut Hall (1992) mengenai teori
Erikson, sejak lahir sampai kematiannya manusia dibentuk dan dipengaruhi oleh
34
lingkungan sosialnya yang berinteraksi secara fisik dan psikologis pada individu.
Oleh karena itu, ada suatu interaksi timbal balik (mutual) antara individu dan
lingkungannya sesuai dengan kapasitas masing-masing dalam mempersiapkan
seorang individu menjadi bagian dari budaya yang sedang berjalan (ongoing
culture).
Pada anak perempuan di keluarga Tionghoa, terdapat berbagai nilai dan
ajaran utama Konfusius yang mempengaruhi bagaimana perempuan diasuh,
dididik dan dipersiapkan untuk memenuhi pandangan mengenai perempuan
tersebut (Meij, 2009). Pada ajaran Konfusianisme sendiri menurut Meij (2009),
identitas diri seseorang merupakan hasil relasinya dengan orang lain sehingga
tidak ada diri yang berdiri sendiri. Dengan demikian, semua tindakan individu
harus berada dalam sebuah bentuk interaksi antara manusia dengan manusia
lainnya. Di dalam ajaran Konfusianisme secara khusus, fungsi dan peran
perempuan adalah subordinat laki-laki.
Pe-nomor-duaan perempuan merupakan sesuatu yang normal dalam tradisi
keluarga Tionghoa. Perempuan pada umumnya tidak dipandang sebagai anggota
keluarga yang berharga bila dibandingkan dengan laki-laki. Budaya patriarki
dalam tradisi keluarga Tionghoa menempatkan perempuan sebagai “liyan” (Meij,
2009). Walaupun tradisi dan budaya Tionghoa memberikan hak istimewa kepada
laki-laki sebagai pembawa nama dan kehormatan keluarga. Namun sebenarnya
perempuanlah yang meneruskan dan mempertahankan tradisi keluarga. Melalui
perempuan, tradisi keluarga dan dipertahankan dan nilai-nilai dalam tradisi
keluarga diinternalisasikan terutama pada anak perempuan.
35
Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Chodorow (1978) dalam “The
Reproduction of Mothering”. Hubungan ibu dan anak perempuannya memiliki
kontinuitas antar generasi yang lebih besar dibandingkan ayah dengan anak laki-
lakinya. Untuk menjaga kontinuitas ini, maka anak perempuan di dalam keluarga
Tionghoa sejak kecil dipersiapkan untuk menghadapi pernikahan serta tunduk
pada otoritas ayahnya dan kemudian pada suaminya ketika sudah menikah
(Sidharta, 1987). Walaupun keluarga Tionghoa di Indonesia pada saat ini sudah
lebih modern daripada masa beberapa puluh tahun yang lalu, namun fokus
terhadap peran tradisional sebagai anak perempuan, istri maupun ibu masih terus
berlanjut sampai sekarang (Sidharta, 1987).
Di masa modern ini, peran tradisional perempuan sebagai anak, istri
maupun ibu di keluarga Tionghoa pun masih tidak dapat dilepaskan dari ajaran
Konfusius. Sikap patuh (obedient) masih dijunjung tinggi dan diharapkan dimiliki
oleh anak perempuan. Oleh karena itu, sikap ini pula yang disosialisasikan pada
anak perempuan dengan harapan akan terinternalisasi di dalam dirinya. Pada
proses sosialisasi dan internalisasi ini, setiap perempuan akan mengacu pada
pengalamannya sebagai anak yang tidak dapat dilepaskan dari peran ibu dalam
mendidiknya. Menurut Chodorow (1978) hubungan antara ibu dan anak
perempuan dapat dideskripsikan sebagai berikut, “the mother experience of her
child and the child’s experience of its mother”
Oleh karena itu, di dalam hal ini ada hubungan interdependensi antara ibu
dengan anak perempuannya. Ibu menganggap anak perempuannya sebagai satu
kesatuan (oneness) dengan dirinya sekaligus perpanjangan (extension) dari dirinya
36
(Chodorow, 1978). Penghayatan seperti ini tentunya akan mempengaruhi fondasi
awal perkembangan psikososial anak yang di dalam teori Erikson disebut sebagai
tahap basic trust vs basic mistrust (Cobb, 1992). Di tahap ini anak sedang belajar
membuat basis atau landasan dari identitas psikososialnya. Melalui relasi dengan
anak perempuan belajar mendefinisikan diri melalui relasi dengan ibunya
(Chodorow, 1978). Bahkan menurut Chodorow (1978) sepanjang kehidupan anak
perempuan nantinya, ia akan terus berusaha menciptakan pengalaman kedekatan
awal dan kebersatuan dengan ibunya. Kualitas dari relasi ibu dengan anak
perempuannya juga akan menjadi penentu sekaligus berinteraksi dengan seluruh
relasi anak perempuan di seluruh tahap perkembangan hidupnya. Chodorow
mengutip kalimat Fairbarn dalam Chodorow (1978) mengenai relasi anak dengan
ibunya sebagai berikut, “the foundation upon which all his/her future relationships
with love objects are based”.
Jika ibu kurang memiliki kesadaran akan identifikasi diri anak perempuan
sebagai entitas yang berbeda dari dirinya atau sebagai perpanjangan dari dirinya,
maka anak pun akan mengalami kebingungan dan kesulitan untuk mengenali
adanya perbedaan dirinya dengan ibunya (Chodorow, 1978). Ibu menjadi simbol
dependensi bagi anak perempuan sehingga untuk dapat bertumbuhkembang
menjadi wanita dewasa, anak perempuan perlu menciptakan diri yang berbeda
dari ibunya. Pada tahapan perkembangan psikososial Erikson, kondisi seperti ini
merupakan tahap dari autonomy vs shame and doubt (Cobb, 1992). Diperlukan
kesadaran ibu untuk mengetahui kapan dan bagaimana ia akan memfasilitasi anak
perempuannya untuk memiliki diri yang berbeda dari dirinya. Ibu harus
37
membimbing anak perempuannya untuk berpisah dan berbeda dari dirinya.
Namun hal ini tidaklah mudah. Terkadang, ibu memunculkan ambivalensi di
dalam diri anak perempuan karena secara tidak langsung mengarahkan anak
perempuan untuk menolak dirinya sekaligus menerima perhatian yang diberikan
oleh ibunya.
Pada tahap-tahap perkembangan anak perempuan selanjutnya pun, ibu
masih tetap berperan penting baginya. Sebab ibu harus peka dan tahu apa yang
dibutuhkan oleh anak perempuannya sekaligus apa yang bisa diperoleh anak
perempuan dari dirinya maupun relasi mereka (Chodorow, 1978). Ibu perlu
mengetahui kapan anak perempuannya sudah siap untuk berjarak dengan dirinya
dan mulai memiliki inisiatif untuk mengurus dirinya sendiri. Transisi pada masa
ini dapat menjadi suatu tahap yang sulit dan membingungkan. Di mana menurut
Erikson, pada tahapan ini anak sedang belajar mengenai initiative vs guilt. Inisiatif
dan otonomi akan memberikan anak perempuan kesempatan untuk memiliki
determinasi dan tujuan. Namun, tanpa memiliki pemahaman yang memadai
tentang tujuan (purpose) dari apa yang dilakukannya terlebih hanya dengan
meniru apa yang dilakukan ibu sebagai perempuan dewasa anak perempuan akan
terjebak dalam ritualisme (Cobb, 1992). Hal ini dapat berlanjut hingga usia
dewasa di mana perempuan sebagai wanita dewasa berusaha menampilkan
gambaran diri yang tidak sesuai dengan diri sejatinya (real-self).
Pada tahapan selanjutnya, ibu dan anak perempuan masih terus
mengembangkan hubungan yang saling melengkapi satu sama lain. Sebab
perempuan memperoleh penghargaan dari lingkungannya serta memenuhi
38
ekspetasi peran sebagai ibu jika mampu melakukan pengasuhan yang baik di mata
lingkungan sosialnya. Ibu berperan ganda sebagai pemberi maupun penerima dari
ekstensi dirinya yang ada pada anak perempuannya (Chodorow, 1978).
Pada lingkungan keluarga Tionghoa yang mengharapkan ibu berperan
penuh dan utama dalam mengasuh dan membesarkan anak, maka anak perempuan
menjadi titik tolak keberhasilan ibu menjalani perannya. Demi penghargaan akan
keberhasilan ini, mungkin saja ibu melakukan apa yang mestinya dilakukan anak
sebagai dirinya sendiri bukan sebagai ekstensi dari diri ibu. Secara langsung
maupun tidak langsung, hal ini akan mempengaruhi tahapan perkembangan
psikososial anak perempuan di masa industry vs inferiority (Hall, 1992).
Di saat yang bersamaan di mana anak perempuan seharusnya
mengembangkan rasa mampu dan kompeten terhadap dirinya sendiri, ibu juga
sedang berusaha untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensinya sebagai ibu
baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sosialnya. Selain hubungan dengan
anaknya, peran pengasuhan ibu juga dipengaruhi oleh hubungannya dengan
suami, pengalaman memiliki ketergantungan finansial, harapan terhadap
keseimbangan dalam perkawinan dan harapannya tentang peran gender itu sendiri
(Chodorow, 1978).
Proses ini terus berlanjut sampai pada tahap di mana anak perempuan
semakin berusaha untuk memantapkan identitas dirinya. Masa ini disebut oleh
Erikson dalam tahapan psikososialnya sebagai identitiy vs identity confusion
(Hall, 1992). Pada masa ini, anak perempuan semakin menyadari identitas dirinya
39
sendiri, yaitu bahwa dirinya adalah pribadi yang unik dan sedang dipersiapkan
untuk menjalani suatu peran yang bermakna di dalam lingkungan masyarakat.
Peran ini dapat dijalaninya dengan menyesuaikan diri ke dalam peran itu atau
melakukan inovasi untuk peran tersebut. Pada perempuan di keluarga Tionghoa
yang telah mengalami sosialisasi identitas sejak masa kecilnya memunculkan
pengalaman sadar (conscious) maupun tidak sadar (unconscious) sepanjang
pengalaman hidupnya. Di masa ini ia memiliki kebebasasn untuk memilih ingin
mendefinisikan dirinya seperi apa di masa sekarang dan apa yang ia harapkan
mengenai dirinya di masa yang akan datang.
Apa yang ia inginkan di masa saat ini maupun di masa yang akan datang,
tidak terlepas dari sejarah dirinya, relasi dirinya dengan ibunya, sejarah ibunya
sendiri maupun sejarah keluarga sebagai bagian dari suatu kelompok kolektif.
Persinggungan dari berbagai elemen ini dapat memunculkan suatu kebingungan
mengenai peran maupun identitas (Hall, 1992). Mudah sekali muncul perasaan
terisolasi, kosong, cemas dan tak berkeputusan terlebih jika ia menuruti dan
menghayati sikap kepatuhan yang disosialisasikan kepadanya sejak ia kecil.
Bahkan terkadang lingkungan sosial terasa menekan mereka untuk membuat
keputusan disertai dengan pertimbangan bagaimana orang lain memandang diri
mereka.
Muncul kemungkinan bahwa krisis identitas dialami oleh perempuan
dalam keluarga Tionghoa seumur hidupnya dalam proses tarik ulur antara diri
ideal dengan diri sejati dan dalam relasinya dengan orang lain. Kebutuhan untuk
mendefinisikan identitas dirinya, berangkat dari kebutuhan manusia untuk merasa
40
menjadi bagian atau milik dari suatu kelompok (Hall, 1992). Di dalam hal ini
perempuan di keluarga Tionghoa memiliki pilihan ingin menjadikan dirinya
bagian dari kelompok apa dan kelompok yang mana. Termasuk apakah ia dan
anak perempuannya berada dalam satu kelompok yang sama atau berbeda.
Penelitian ini ingin menelaah secara eksploratif mengenai proses
pembentukan identitas termasuk krisis identitas yang dialami perempuan di
keluarga Tionghoa Indonesia sebagai ibu maupun anak perempuan yang
mengalami perilaku berbeda secara ganda, pertama karena keperempuanannya di
dalam budaya patriarki Tionghoa dan kedua karena ke-Tionghoan-nya di dalam
konteks kehidupan di Indonesia.
II. B. Kerangka Penelitian
Alur berpikir dan dinamika teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut.
41
Gambar II.B.1. Dinamika Teori Penelitian
Social learning theory dan
psikodinamika ibu-anak
perempuan (Chodorow, 1978)
42
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
III.A. Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola asuh
membentuk identitas gender ibu-anak perempuan di keluarga Tionghoa.
Gambaran pola asuh antara ibu-anak perempuan merupakan konteks dari
pengalaman hidup ibu sebagai perempuan yang memunculkan identitas gender
sebagai salah satu hasil dari pola asuh tersebut. Pengalaman hidup yang
diimplementasikan dalam pola asuh akan terus berulang dan terjadi terus menerus
di dalam keluarga dan masyarakat yang bersumber dari pengalaman hidup
individu.
Penelitian ini ingin melihat bagaimana pemaknaan ibu dan anak
perempuan di keluarga Tionghoa terhadap identitas gendernya yang
ditransmisikan melalui interaksi di dalam pola asuh. Penelitian ini menggunakan
keluarga Tionghoa sebagai konteks sosial budaya yang mempengaruhi paradigma
identitas gender di kelompok masyarakat tersebut. Proses pola asuh dan
pembentukan identitas gender dilihat sebagai suatu proses yang
berkesinambungan dari ibu ke anak perempuan secara turun temurun dengan
berbagai aspek yang meliputi mereka sehingga diperlukan cara berpikir holistik
untuk dapat menangkap kekayaan dan keragaman data.
43
Berdasarkan penjelasan di atas mengenai penelitian yang ingin melihat
makna di dalam konteks dan cara berpikir holistik, maka penelitian ini termasuk
dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut Poerwandari (2008), penelitian
kualitatif memungkinkan munculnya pemahaman mengenai kompleksitas
perilaku dan penghayatan manusia sebab di dalam penelitian kualitatif, peneliti
memperlakukan manusia secara empatis sebagai makhluk yang memiliki
kesadaran dan pemahaman mengenai hidupnya sendiri. Menurut Creswell (2009)
penelitian kualitatif mengandung pengertian adanya penggalian dan pemahaman
makna terhadap apa yang terjadi pada individu maupun kelompok.
Selain itu, ciri-ciri dari penelitian kualitatif yang dipaparkan oleh
Poerwandari (2008) sesuai dengan karakteristik dan tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini. Ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain mendasarkan diri
pada kekuatan narasi, melakukan studi dalam situasi alamiah, analisis bersifat
induktif karena berorientasi pada eksplorasi, penemuan dan logika induktif
sehingga pada akhirnya ditemukan pola hubungan dari kategori yang ada (Patton
dalam Poerwandari, 2008). Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk memperoleh
pemahaman menyeluruh dan utuh mengenai fenomena yang diteliti dengan
mengasumsikan bahwa keseluruhan fenomena adalah suatu sistem yang
kompleks.
Berdasarkan pemaparan masalah di bagian latar belakang dan perumusan
masalah, dapat terlihat bahwa proses sosialisasi peran gender ini merupakan suatu
hal yang kompleks karena terjadi di berbagai tingkatan dan aspek kehidupan
antara ibu dengan anak maupun sebaliknya. Atas dasar kompleksitas inilah
44
diperlukan proses penelitian sirkuler sehingga proses penelitian mengenai peran
ibu dalam proses sosialisasi peran gender ini dapat ditelaah dengan baik.
Penelitian dengan topik ini belum pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia
sehingga pertanyaan-pertanyaan khas pendekatan kualitaitf yang terbuka (open-
ended) diharapkan dapat menampung kekayaan dan kedalaman informasi yang
diperoleh dari para narasumber untuk diteruskan pada penelitian-penelitian
selanjutnya.
Penelitian kualitatif ini akan menggunakan paradigma kritikal sebab peneliti
menyadari bahwa berbagai kondisi sosial ekonomi mempengaruhi kehidupan
perempuan dalam usahanya untuk menghayati proses kehidupannya. Pada
paradigma ini, manusia dilihat memiliki kemampuan untuk memberikan
(menciptakan) arti terhadap kehidupan yang dialami, bahkan mampu mengubah
arti tersebut (Poerwandari, 2008). Dengan demikian, peneliti menyadari bahwa
ilmu tidak dapat dipisahkan dari nilai yang hidup di dalam masyarakat. Menurut
Poerwandari (2008), paradigma kritikal merupakan pendekatan yang cocok
digunakan untuk penelitian tentang perempuan.
Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
(Kumar, 1999). Sebab penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu
deskripsi atau gambaran mengenai proses sosialisasi gender dari ibu kepada anak
remaja perempuannya sehingga pada akhirnya ditemukan suatu siklus proses
sosialisasi yang berguna untuk memahami proses sosialisasi peran gender. Di
dalam penelitian deskriptif ini, tidak ada hipotesis awal yang digunakan.
45
III.B. Instrumen Penelitian
Berdasarkan jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini, maka pengumpulan data untuk penelitian ini akan menggunakan wawancara
dengan pedoman terstandar terbuka. Menurut Patton (dalam Poerwandari, 2008),
wawancara dengan pedoman terstandar terbuka adalah wawancara yang ditulis
rinci lengkap dengan set pertanyaan. Peneliti melaksanakan wawancara sesuai
sekuensi yang tercantum dan menanyakan dengan cara yang sama pada responden
yang berbeda. Namun untuk menggali jawaban yang terbatas digunakan
keluwesan peneliti untuk menggali data lebih dalam sesuai dengan karakteristik
responden. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pemahaman dan
penghayatan subyek terhadap tema-tema yang terkait dengan penelitian ini.
Selain wawancara terstandar terbuka, instrumen lain yang digunakan dalam
penelitian ini adalah alat perekam. Alat perekam ini akan digunakan selama
proses wawancara berlangsung dan akan digunakan sesuai dengan izin subjek.
Sebelum dilakukan proses perekaman wawancara, subjek akan diminta untuk
mengisi lembar informed consent sebagai pernyataan kesediaan berpartisipasi di
dalam penelitian ini serta bersedia dilakukan proses perekaman terhadap
pengambilan data menggunakan teknik wawancara ini.
Menggunakan pendekatan dan paradigma seperti ini, maka metodologi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman
(verstehen) daripada pengukuran (Poerwandari, 2008).
III.C. Subjek Penelitian
46
III. C.1. Karakteristik Subjek
Subjek di dalam penelitian ini adalah ibu dan anak perempuan dari keluarga
Tionghoa Indonesia peranakan yang tinggal di Jakarta dengan kriteria sebagai
berikut :
Berbahasa Indonesia dalam interaksi sehari-hari antara ibu dan anak
perempuan.
Usia anak perempuan adalah dewasa muda (early adulthood) yaitu antara 20-
25 tahun (Santrock, 2008).
Pada usia dewasa muda, perempuan sedang memasuki tahap persiapan untuk
menikah dan menjadi ibu. Selain itu, identitas gender yang terbentuk relatif
sudah lebih kokoh dibandingkan remaja perempuan. Diharapkan hal ini
membuat subjek dapat lebih merefleksikan hidupnya.
Ibu dan anak perempuan tinggal bersama di dalam satu rumah dan dipastikan
bahwa ibu merupakan pengasuh utama anak
Ibu dari anak perempuan tersebut merupakan ibu rumah tangga.
III.D. Prosedur Penelitian
III.D.1. Tahap Persiapan
Pada bulan Januari 2012, peneliti mulai membuat panduan wawancara
berdasarkan kerangka teori yang telah dikumpulkan. Panduan wawancara memuat
pertanyaan peneliti yang terdiri dari latar belakang kehidupan subjek dan
pertanyaan-pertanyaan yang dibagi dalam empat aspek, yaitu gender, social-
learning, psikodinamika dan relasi ibu-anak perempuan. Melalui uji coba pada
47
responden dengan karakteristik serupa subjek penelitian dan umpan balik dari
dosen pembimbing dilakukan revisi pada panduan wawancara.
Akhir bulan Januari 2012 dihasilkan panduan wawancara yang telah
diperbaharui. Panduan wawancara ini menggunakan tahapan atau fase kehidupan
(sequence of life) untuk menggali data dari subjek. Alur pertanyaan menjadi lebih
kronologis dan mudah dipahami subjek. Panduan wawancara yang telah
diperbaharui ini diuji-cobakan pada pasangan ibu dan anak perempuan yang
sesuai dengan karakteristik penelitian ini.
Pencarian subjek penelitian telah dilakukan sejak bulan Desember 2012.
Pada pertengahan bulan Februari hingga pertengahan bulan April 2012 dilakukan
pengambilan data yang akhirnya menghasilkan data dari dua pasang ibu dan anak
perempuan keluarga Tionghoa. Peneliti melakukan initial contact dengan para
subjek penelitian dan menyiapkan informed consent sebagai bukti kesediaan
subjek untuk berpartisipasi dalam penelitian ini serta menyiapkan alat perekam.
III.D. 2. Cara Memperoleh Subjek
Subjek yang terlibat dalam penelitian ini pada akhirnya adalah dua pasang
ibu dan anak perempuan. Pencarian subjek dilakukan dengan bertanya pada
orang-orang di sekitar peneliti yang terdiri dari ibu, keluarga dan teman-teman
peneliti. Dari rekomendasi dan pertimbangan yang diberikan, peneliti melakukan
initial contact dengan calon subjek. Peneliti mengalami kesulitan untuk mencari
pasangan ibu dan anak perempuan yang bersedia untuk menjadi subjek penelitian.
48
Sebagian besar kendala ada pada ibu di mana mereka merasa keberatan
untuk menjadi subjek penelitian, sementara anak perempuan mereka sudah
bersedia untuk diwawancara. Ada juga ibu yang keberatan karena ia merasa sudah
tidak terlalu lekat dengan budaya Tionghoa sehingga takut tidak
merepresentasikan keluarga Tionghoa pada umumnya. Selain itu menentukan
waktu untuk mewawancarai subjek juga menjadi kendala tersendiri. Akhirnya
peneliti mengubah cara mencari subjek penelitian, yaitu dengan menghubungi
para ibu terlebih dahulu.
Di tengah kesulitan mencari subjek penelitian, ibu peneliti berinisiatif
melakukan rekomendasi dan initial contact pada orang-orang yang dirasa sesuai
dengan karakteristik subjek penelitian. Selanjutnya peneliti yang melakukan
initial contact dan membuat janji untuk mewawancarai. Peneliti menyadari ibu
peneliti memberikan akses untuk membuat para subjek penelitian bersedia terlibat
dalam penelitian ini. Hal ini bisa disebabkan karena kesamaan latar belakang etnis
maupun hubungan interpersonal yang telah lebih lama terjalin.
Subjek pertama, Ibu Lely merupakan ibu dari teman kerja ibu peneliti yang
kebetulan memiliki karakteristik sesuai dengan penelitian ini. Ibu Lely juga
memiliki anak perempuan, Retha, sesuai dengan karakteristik usia anak
perempuan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan terlebih dahulu pada Ibu
Lely kemudian dengan Retha pada waktu dan tempat yang terpisah.
Subjek kedua, Ibu Olga merupakan kerabat jauh dari peneliti yang
memiliki karakteristik sesuai dengan penelitian ini. Ia juga memiliki anak
49
perempuan, Shinta, sesuai dengan karakteristik usia anak perempuan dalam
penelitian ini. Wawancara dilakukan di rumah Ibu Olga pada waktu yang terpisah.
III.D.3. Tahap Pelaksanaan
Setelah subjek menyatakan kesediaannya untuk diwawancarai, peneliti dan
subjek membuat janji untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu dan
tempat yang disepakati. Sebelum wawancara, peneliti melakukan konfirmasi
kembali mengenai janji wawancara. Peneliti juga menyiapkan alat perekam,
informed consent dan panduan wawancara. Saat bertemu subjek, peneliti menjalin
rapport terlebih dahulu, meminta izin menggunakan alat perekam selama
wawancara lalu memulai wawancara menggunakan panduan yang telah dibuat
sebelumnya.
Adapun pelaksanaan wawancara adalah sebagai berikut :
Subjek Hari/Tanggal Tempat Durasi
Ibu Lely Sabtu, 25 Februari
2012
Foodcourt ITC
Kuningan, Jakarta
Selatan.
96 menit
(10. 55-11.51 WIB)
Kamis, 8 Maret
2012
Rumah Duka
Husada, Jakarta
Barat
18.30-20.00
(mengobrol di luar
wawancara saat
menunggu Retha,
anak
perempuannya
selesai bertugas
memotret pada
acara pemakaman
50
kerabat mereka)
Minggu, 15 April
2012
Rumah anak
pertama Ibu Lely
di Bekasi, Jakarta
Timur
60 menit
(09.48-10.48 WIB)
Retha Kamis, 8 Maret
2012
Rumah Duka
Husada, Jakarta
Barat
45 menit
(20.56-21.41 WIB
Minggu, 15 April
2012
Rumah anak
pertama Ibu Lely
(kakak Retha) di
Bekasi, Jakarta
Timur
60 menit
(11.00-12.00 WIB)
Ibu Olga Minggu, 18 Maret
2012
Rumah Ibu Olga
di Kelapa Gading,
Jakarta Utara
60 menit
(16.48-17.48)
Minggu, 8 April
2012
Rumah Ibu Olga
di Kelapa Gading,
Jakarta Utara
60 menit
(11.16-12.16)
Shinta Minggu, 18 Maret
2012
Rumah Ibu Olga
di Kelapa Gading,
Jakarta Utara
60 menit
(18.00-19.00)
Minggu, 8 April
2012
Rumah Ibu Olga
di Kelapa Gading,
Jakarta Utara
45 menit
(12.30-13.15)
Pada wawancara terakhir dengan Ibu Lely dan Retha, peneliti
menghabiskan setengah hari berinteraksi dengan keluarga mereka di rumah anak
pertama Ibu Lely. Peneliti bermain dengan cucu Ibu Lely dan berbincang-bincang
51
santai dengan Ibu Lely maupun Retha. Pada wawancara terakhir dengan Ibu Olga
dan Shinta, peneliti menghabiskan setengah hari di rumah keluarga Ibu Olga dan
diakhiri dengan makan bersama keluarga Ibu Olga.
III.E. Metode Analisis Data
Tahap analisis dan interpretasi data dilakukan dengan membuat transkrip
verbatim dari rekaman wawancara. Data verbatim ini berguna untuk mengolah
data lebih lanjut. Selain membuat verbatim, peneliti juga membuat timeline
kehidupan para subjek sehingga dapat mengetahui urutan kronologis peristiwa
hidup subjek. Setelah semua rekaman wawancara selesai dibuat dalam bentuk
verbatim, peneliti mengelompokkan dan membuat coding dari data yang ada.
Coding ini menghasilkan tema-tema sesuai dengan teori.
Lalu data verbatim ibu-anak perempuan dikelompokkan dan dibandingkan
dalam satu tabel berdasarkan kesamaan tema. Melalui cara seperti ini dapat
terlihat bagaimana dinamika ibu-anak perempuan dalam memahami dan
menghayati suatu tema yang sama. Dari pembuatan tabel perbandingan ini,
peneliti dapat memetakan bagian mana yang masih belum lengkap sehingga
dilakukan wawancara kedua untuk melengkapi data. Tabel perbandingan antar
subjek ini digunakan untuk membuat analisa dan interpretasi terhadap hasil
penelitian.
52
BAB IV
HASIL PENELITIAN
IV.A. Deskripsi Latar Belakang Subyek
Berdasarkan kode etik penelitian, maka identitas subyek ibu dan anak
perempuan dalam penelitian ini dirahasiakan dan ditulis menggunakan nama
samaran. Secara umum, gambaran karakteristik subyek dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
Tabel IV.A.1. Deskripsi Latar Belakang Subyek
Subyek Pertama
Ibu Anak Perempuan
Nama Samaran Lely Retha
Tempat/Tgl Lahir Jakarta, 16 Mei 1958 Jakarta, 9 April 1990
Jenis Kelamin Perempuan Perempuan
Suku Bangsa Tionghoa, generasi ke-2 Tionghoa, generasi ke-3
Agama Katolik, dibaptis umur 24 tahun Katolik, dibaptis bayi
Pendidikan D1 Bahasa Mandarin S1 Desain Komunikasi Visual
Pekerjaan Karyawan accounting Freelance
Domisili Pamulang Pamulang
Anak ke- 4 dari 11 bersaudara 2 dari 3 bersaudara
Hobi Bercocok tanam Fotografi, melukis
Subyek Kedua
Ibu Anak Perempuan
Nama Samaran Olga Shinta
Tempat/Tgl Lahir Jakarta, 8 Oktober 1966 Jakarta, 6 April 1988
Jenis Kelamin Perempuan Perempuan
Suku Bangsa Tionghoa, generasi ke-3 Tionghoa, generasi ke-4
Agama Katolik Katolik, dibaptis bayi
Pendidikan SMK Pariwisata S1 Financial Accounting
Pekerjaan Wirausaha Karyawan
Domisili Kelapa Gading Kelapa Gading
Anak ke- 5 dari 6 bersaudara 1 dari 3 bersaudara
Hobi Membaca buku Wisata kuliner
53
IV.B. Hasil Temuan Data Penelitian
IV.B.1. Subyek Pertama
IV.B.1.1 Latar Belakang Ibu Subyek Pertama
Ibu Lely merupakan anak ke-4 dari sebelas bersaudara keluarga Tionghoa
generasi kedua bermarga Tjong di Indonesia dari garis ayahnya. Ibu dari Ibu Lely
menghabiskan masa kecilnya di Cina daratan dan baru tinggal di Jakarta sejak
usia 18 tahun. Ayahnya memenuhi kebutuhan keluarga dengan berjualan di
warung dekat rumah sementara ibunya secara penuh menjalani peran sebagai ibu
rumah tangga yang mengurus kesebelas anaknya (satu meninggal sewaktu bayi).
Ibu Lely menghabiskan masa kecil di daerah Jatinegara sampai sebelum ia
menikah di usia 24 tahun. Saat masih remaja, Ibu Lely menilai ibunya sebagai
orang yang terlalu keras karena terlalu banyak melarang, galak dan sering
mengomel. Oleh ibunya, sejak masih usia sekolah Ibu Lely diharuskan
mengerjakan pekerjaan rumah tangga mengurus dan membersihkan rumah
bersama dengan saudara-saudara perempuannya yang lain. Sementara saudara
laki-lakinya diperbolehkan tidak mengurus rumah dan bermain di luar rumah.
Ibu Lely sebenarnya ingin bisa bermain dan berkegiatan seperti itu, namun
apa daya pekerjaan rumah yang banyak membuat Ibu Lely harus segera pulang ke
rumah sehabis pulang sekolah. Ibu Lely menyadari betapa sibuk ibunya dalam
mengurus rumah tangga dan sepuluh anak. Maka sebagai anak perempuan ia
membantu membersihkan rumah dan mengurus kebutuhan rumah tangga.
54
Ibu Lely menuturkan bahwa dulu sehabis sekolah ia tidak diperkenankan
mengikuti kegiatan apapun karena harus membantu di rumah. Ibu Lely pernah
mengikuti latihan drum band di hari Minggu. Namun ia hanya bisa dua sampai
tiga kali mengikuti latihan. Latihan-latihan selanjutnya tidak bisa ia ikuti karena
latihan dilakukan di luar jam sekolah. Menurut Ibu Lely, sampai sekarang ia
masih hafal memainkan sebaris nada yang pernah ia pelajari dahulu ketika
mengikuti kegiatan drum band.
Ibu Lely menilai ibunya sebagai sosok yang kolot, kaku dan keras.
Menurutnya hal ini dipengaruhi oleh latar belakang ibunya yang sejak kecil telah
ditinggal oleh orang tuanya. Orang tua dari ibunya telah merantau terlebih dahulu
ke Indonesia, baru kemudian pada saat berumur 18 tahun ibunya menyusul ke
Jakarta. Ibu Lely merasa dirinya yang terbentuk hingga hari ini merupakan hasil
didikan ibunya yang kaku. Saat ini ketika anak-anak dari Ibu Lely suka mengeluh
ibu mereka kaku, ia menyadari kemungkinan disebabkan oleh didikan ibunya
kepada Ibu Lely yang kaku.
Pada zaman Ibu Lely dididik oleh ibunya, banyak aturan-aturan yang
kaku. Tidak ada tawar menawar untuk aturan yang sudah ditetapkan untuk anak-
anak. Anak-anak pun tidak diperkenankan bertanya atau membantah apa yang
sudah diperintahkan oleh orang tua. Bagi orang tua, yang penting anak-anak
mematuhi dan menjalankan apa yang mereka perintahkan.
Sosok ayah digambarkan Ibu Lely sebagai orang yang lebih sabar dan
tidak sekaku ibunya. Sewaktu kecil ia merasa ayahnya adalah ayah yang baik dan
55
tidak pernah marah. Ayah dari Ibu Lely selalu mengurusi kebutuhan sekolah dan
datang pada pertemuan sekolah anak-anaknya. Menurut Ibu Lely, hal ini
dikarenakan ibunya tidak lancar berbahasa Indonesia terutama dalam hal berbicara
dan baca-tulis sehingga ayahnya yang lebih sering berurusan dengan pihak
sekolah.
Perubahan pandangan terhadap ibunya dirasakan Ibu Lely setelah ia
menikah. Baru pada masa setelah menikah, ia dapat berterima kasih terhadap
ajaran dan didikan ibunya. Ia menjadi lebih memahami kekhawatiran orang tua
terutama ibunya. Hal-hal yang diajarkan oleh ibunya juga terasa berguna ketika ia
sudah menikah. Bahkan muncul perasaan bersalah pada dirinya ketika ibunya
meninggal terlalu cepat. Ibunya meninggal karena kanker payudara pada tahun
1997 tanpa sempat mengalami kebersamaan yang menyenangkan ketika anak-
anaknya sudah mulai mapan dalam hal kehidupan dan finansial.
Ibu Lely bertemu dengan suaminya dalam kegiatan di gereja. Sebelum
pernikahan ia dibaptis menjadi Katolik sekaligus mengalami naturalisasi
kewarganegaraan dan pergantian nama. Status suaminya yang sudah Warga
Negara Indonesia (WNI) memudahkan proses naturalisasi ini. Setelah menikah ia
sempat mengikuti kursus tata buku (akuntansi) di YAI. Kursusnya ini tidak selesai
karena ia hamil anak pertama dan sering mual-mual hebat sehingga akhirnya ia
berhenti kursus. Selama setahun ia tinggal di daerah Gang Pedati di Jatinegara.
Setahun kemudian ia menyusul suami yang bertugas di Cilacap. Anak pertamanya
lahir pada tanggal 21 Januari 1984. Sedangkan anak kedua dan ketiga lahir pada
tahun 9 April 1990 dan 12 November 1993.
56
Pada tahun 2002, di usia 44 tahun Ibu Lely berhenti bekerja dan
memutuskan untuk mengambil kuliah D1 Bahasa Mandarin. Beliau menjadi
lulusan terbaik bukan hanya untuk angkatannya saja, tapi untuk keseluruhan
angkatan di sekolah tersebut. Kemampuan berbahasa Mandarin ini menjadi modal
baginya untuk memberikan kursus Mandarin pada anak-anak di daerah tempat
tinggalnya. Dari hari Senin sampai Sabtu Ibu Lely memberi kursus pada anak-
anak dan uang yang terkumpul menjadi biaya untuk menghidupi keluarga
terutama ketika suaminya terkena stroke. Sejak tahun 2009 sampai sekarang ia
kembali bekerja di perusahaan. Berangur-angsur suaminya pun pulih dan dapat
bekerja kembali.
IV.B.1.2 Latar Belakang Anak Perempuan Subyek Pertama
Retha merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Ia mempunyai kakak
perempuan yang terpaut usia empat tahun dan adik perempuan yang usianya
terpaut tiga tahun. Ia menghabiskan hidupnya sampai saat ini tinggal di daerah
Pamulang dan bersekolah di sekolah Katolik dekat rumahnya dari TK-SMA.
Semasa usia TK-SD ibunya bekerja hingga malam sehingga ia banyak diasuh oleh
pembantu di rumah.
Retha merasa dirinya sewaktu kecil adalah anak yang bandel karena susah
makan. Menurutnya, ia tidak berselera makan karena masakan pembantunya yang
bercita rasa manis seperti masakan Jawa pada umumnya, sementara masakan
ibunya tidak seperti itu. Ia juga sering tidak tidur siang padahal disuruh oleh
ibunya.
57
Di malam hari, sepulang ibunya bekerja tugas-tugas sekolah Retha akan
dilihat oleh ibunya. Sampai kelas tiga SD, ibunya juga masih mengawasi dan
menemaninya dalam belajar. Pada suatu kesempatan, ibunya pernah menyabet
betis Retha dengan sapu lidi jika ia tidak serius dalam belajar. Namun
menurutnya, hal ini hanya dilakukan oleh ibu Lely pada dirinya saja. Pada masa
sekolah selanjutnya ia terbiasa belajar mandiri namun sesekali ibunya masih
menanyakan tentang perkembangan akademisnya.
Saat memasuki usia SMP, ayahnya mengalami stroke dan ibu Lely
berhenti bekerja. Kehadiran ibunya di rumah menyebabkan ia memiliki lebih
banyak waktu untuk mengobrol dengan ibunya. Ia pun jadi merasa lebih dekat
dengan ibunya di masa ini. Prestasi sekolah yang semasa SD hanya sepuluh besar
pun meningkat menjadi tiga besar karena dimonitor langsung oleh ibunya.
Menurut Retha, ibunya juga mengurus ayahnya yang mengalami stroke termasuk
melatih kemampuan motorik sang ayah mulai dari makan, berjalan, menulis,
membaca dan mengucapkan kata. Sambil mengurus anak-anak dan suami, ibu
mengambil kursus bahasa Mandarin yang kemudian menjadi mata pencaharian
utama keluarga sampai Retha memasuki masa SMA.
Selepas lulus SMA, Retha masuk ke jurusan Desain Komunikasi Visual
yang diinginkannya. Ia tidak diperbolehkan untuk menyewa kamar kos yang dekat
dengan kampusnya. Kedua orang tuanya menginginkan ia tetap pulang ke rumah
setiap hari walaupun jarak tempuh antara kampus dan rumahnya memakan waktu
dua jam setiap kali jalan. Ibunya juga tidak dengan mudah memperbolehkan
Retha menginap di rumah temannya. Biasanya Retha akan menginap di rumah
58
temannya jika pulang terlalu malam dari kampus dan sudak tidak ada angkutan
umum menuju rumahnya. Atau, jika ia sedang kerja kelompok dan keesokan
paginya harus mengikuti kelas di pagi hari. Pada waktu ia akan menginap di
rumah temannya, Retha akan memberitahu ibunya. Kemudian ibunya akan
bertanya di rumah siapa ia akan menginap dan siapa saja yang menginap
bersamanya. Jika teman-teman Retha tidak dikenal oleh ibunya, maka ia tidak
diperbolehkan menginap. Kemudian, ibunya akan berbicara dengan teman dari
Retha tersebut untuk mengkonfirmasi bahwa anaknya memang menginap di
rumah temannya.
Empat tahun yang lalu, Ibu Lely kembali bekerja kantoran setelah selama
enam tahun menghidupi keluarga dengan menjadi guru kursus Mandarin. Setahun
yang lalu kakak perempuan dari Retha menikah pada usia dua puluh enam tahun
dan meninggalkan rumah untuk hidup bersama dengan keluarga barunya.
Kakak perempuan Retha menikah dengan laki-laki keturunan Manado-
Jawa. Namun ibu dari Retha tetap menginginkan pernikahan menggunakan tata
cara dan adat Tionghoa. Sekarang ini setelah kepergian kakak perempuannya,
Retha banyak menggantikan tugas cicinya untuk mengurus dan memasak di
rumah. Bulan Februari yang lalu, Retha baru saja meraih gelar sarja di bidang
Desain Komunikasi Visual dengan kekhususan Desain Grafis.
IV.B.1. 3. Pengalaman Ibu sebagai Anak Perempuan di Keluarga Tionghoa
Ibu Lely sebagai anak keempat dari 10 bersaudara bertugas membantu
ibunya dalam mengurus kebutuhan rumah tangga. Mereka tidak punya pembantu
59
sehingga segala urusan rumah tangga dikerjakan sendiri oleh ibu dan anak-anak
perempuan. Ibu Lely melihat ibunya terus menerus terokupasi dengan pekerjaan-
pekerjaan rumah. Anak-anak yang sudah lebih besar dikerahkan untuk ikut
membantu, salah satunya adalah Ibu Lely. Ibu Lely menghabiskan waktunya di
luar waktu sekolah untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Sebenarnya, ia ingin
sekali bisa mengikuti aktivitas di luar rumah seperti ekskul Drum Band yang
diadakan sekolahnya setiap hari Minggu. Namun karena kegiatan ini dilakukan di
luar jam sekolah maka Ibu Lely tidak dapat mengikutinya.
Sewaktu kecil, Ibu Lely merasa ibunya sebagai orang tua yang kolot, galak
dan cerewet serta tidak pandai bergaul. Ibu Lely merasa ibunya banyak mengatur
dan mengekang serta terlalu banyak melarang. Kebebasan sebagai anak
perempuan jarang ia rasakan. Sementara ia melihat sendiri bagaimana saudara
laki-lakinya diperbolehkan bermain dengan bebas dan tidak dibebankan tugas
membersihkan rumah seperti anak-anak perempuan.
Kalo anak perempuan, kerjaannya nggak berenti...nyapu, ngepel, nyuci
baju...Kalau anak laki, boleh tinggal makan...nggak usah ngapa-
ngapain...sampe kita nimba...pokoknya anak perempuan terus yang
kerja...Kalo anak laki, boleh ongkang-ongkang...Itu yang paling tante rasa
beda...
Ibu Lely juga sangat senang bersekolah. Sebenarnya ia ingin bersekolah
tinggi. Namun ketiadaan biaya membuatnya harus mengurungkan niatnya ini.
Selepas SMA Ibu Lely tahu bahwa ia tidak mungkin melanjutkan sekolah dan
harus bekerja. Ketika pada masa SMA ia mengalami penambahan waktu sekolah
berdasarkan aturan pemerintah, ia merasa senang sekali bisa memperlama waktu
60
sekolahnya. Padahal teman-temannya yang lain protes dan merasa keberatan
dengan penambahan lama sekolah ini. Tak lama setelah mulai bekerja, Ibu Lely
berkenalan dan kemudian menikah dengan suaminya pada umur dua puluh empat
tahun.
IV.B.1.4. Kesadaran akan Adanya Perubahan Nilai-nilai yang
Disosialisasikan
Ibu Lely menyadari adanya perubahan nilai-nilai dari yang ia alami
sebagai anak perempuan dengan apa yang ia tanamkan sebagai ibu kepada anak-
anak perempuannya. Ia merasa perubahan ini merupakan hasil dari
pengalamannya sebagai anak perempuan. Perubahan paling besar yang dirasakan
dan disosialisasikan terkait dengan kebebasan untuk beraktivitas dan
mengaktualisasikan diri dalam berbagai kegiatan.
Nggak tau deh tradisi atau nggak, saya mah ngejalanin hidup ngalir aja.
Apa yang bagus saya sampekan, yang dulu saya merasa saya nggak
nyaman saya ngga terapin. Apa yang dulu saya ngerasa saya kepengen
gini gini...saya coba berusaha kasih kebebasan ke anak-anak.
Retha menyadari adanya perubahan nilai yang disosialisasikan. Ia juga
mengetahui perubahan ini terjadi karena ibunya merasa ada hal-hal yang tidak
cocok dari pendidikan yang diberikan oleh popo (Ibu dari ibunya) terhadap
ibunya. Pengetahuan dan kesadaran ini membantu Retha untuk memahami
mengapa ibunya mendidik dan mendorong anak-anaknya seperti sekarang ini
untuk berkegiatan dan beraktivitas di luar rumah.
Kan mama berasa juga ya, dulu waktu sama Popo mama kan juga ada
yang nggak sreg. Kayak ya dia kan pengen keluar, pengen main sama
61
temen-temennya. Malu kalo harus di rumah terus, kuper
berasanya...Mama nggak mau anak-anaknya kuper. Makanya didorong
keluar, tapi dikontrol. Terus kayak organisasi, dulu mama ee...Popo itu
kan Chinesenya masih kentel sekali, jadi kalo dia tuh pegang, yang boleh
keluar tuh cuma anak cowo. Yang boleh ngapa-ngapain itu cuma anak
cowok. Dibela-belain sekolah ya anak cowo. Nah mama nggak mau kayak
gitu...jadi kan mama kebetulan punya anak perempuan semua, kita semua
apa ya...didorong untuk ikut organisasi-organisasi...biar nggak pemalu...
Mama kan merasa dia pemalu...
Ibu Lely menyadari adanya perbedaan cara mendidik antara anak pertama,
kedua dan ketiga walaupun sama-sama perempuan. Hal ini juga dirasakan oleh
Retha. Perbedaan ini berlandaskan prinsip yang dianut oleh Ibu Lely.
Prinsip tante gini lho...anak pertama harus dipegang sekali...Kalo anak
pertama sudah dipegang dengan baik, adik-adiknya udah tinggal ngikut.
Kalo anak pertama aja udah lepas, adiknya...kita mau ngajarin apapun
juga nggak ada guna...”itu kakak boleh, itu cici boleh, itu koko boleh”
gitu kan...anak pertama mau tidak mau harus kita pegang...semua hal
yang baik harus kita tanamkan. Kan nanti adiknya cuma liat contoh
kan...kalo ngeliat cicinya baik, udah nggak pake bilang “kok cici boleh,
aku nggak boleh, ma?” Sekarang malah kebalik...jadi, kakaknya yang
complain...”kok adeknya lebih longgar” (tertawa).
Secara spesifik, Retha merasa perbedaan ini muncul dalam keleluasaan untuk
menginap di rumah teman. Pada masa kakak perempuannya bersekolah, ia sama
sekali tidak diperkenankan untuk menginap di rumah temannya. Sementara Retha
diperbolehkan menginap dalam kondisi mendesak.
Iya. Cici kan dulu nggak boleh nginep sama sekali, nggak pernah sama
sekali...nggak boleh. Mau mama orangnya kenal pun, nggak boleh...kalo
aku masih boleh nginep tapi kalo bener-bener mepet, harus
nginep...banget...baru boleh nginep.
62
IV.B.1.5. Sosialisasi Identitas Gender pada Anak Perempuan
Ibu Lely merasa hal yang paling sering ia tanamkan kepada anak-anak
perempuannya adalah nilai kepercayaan. Sebab menurutnya kepercayaan adalah
suatu hal yang tidak bisa dibeli, sekaya apapun seseorang. Ia mewanti-wanti
jangan sampai kepercayaan tersebut dirusak. Ia juga menekankan pentingnya
ketepatan waktu.
Kalo kita udah janji sama orang, kita harus tepati...itu yang paling saya
tekankan ke anak-anak.
Hal serupa juga dirasakan oleh Retha. Ia merasa ibunnya menekankan nilai
kepercayaan ini kepada dirinya. Namun Retha memiliki pemaknaan yang berbeda
tentang kepercayaan yang ditanamkan oleh ibunya.
Ini sih kepercayaan...Mama kan orangnya...kalo Popo ke mama, mama
tuh ngak boleh ke mana-mana waktu dulu, waktu muda...nggak boleh
pergi-pergi...kalo aku boleh, selama mama tahu aku pergi sama
siapa...pulang jam berapa sama siapa. Eh pernah aku pulang jam tiga
pagi, tapi pulangnya dari gereja. Asal ngabarin sih mama gapapa.
Retha memaknai kepercayaan yang diberikan oleh ibunya sebagai kepercayaan
untuk beraktivitas di luar rumah. Kepercayaan ini merupakan hasil dari
pengalaman ibunya yang dahulu tidak diperbolehkan bepergian ke mana-mana
oleh ibunya. Retha juga merasa ibunya mengajarkan nilai kedisiplinan padanya.
Namun ia merasa ibunya tidak sekeras itu menanamkan kedisiplinan pada adiknya
yang merupakan anak ketiga.
63
Retha merasa sangat ditanamkan kedisiplinan oleh ibunya, terutama dalam
hal belajar.
Orang Chinese kan disiplin banget...apalagi kalo soal belajar itu mama
disiplin banget...Waktu aku SD tuh bener-bener...kalo pr belum selesai,
nggak boleh tidur. Trus setiap aku sakit, aku mau bolos kan kalo
sakit...biasanya bawaannya males kan...kalo kata mama tuh, kalo belum
pingsan itu masih harus masuk sekolah.
Sementara dari segi afeksi, Retha merasa ibunya bukanlah sosok ibu yang
sering memeluk atau melakukan kontak fisik dengan anaknya. Menurut Retha, hal
ini disebabkan karena ibunya dulu mendapat didikan dari ibunya seperti ini.
Mama tuh tipe orang yang jarang peluk-peluk orang...karena Popo
mungkin juga gitu. Popo anaknya banyak sekali, jadi dia jarang kontak
fisik sama anaknya...mungkin mama nggak terbiasa juga kontak fisik sama
anaknya.
Retha juga menyadari seiring dengan perkembangannya bahwa ia lebih
mendapatkan pendidikan seksualitas dari sekolah. Ia merasa beruntung bersekolah
di sekolah yang memberikan pendidikan seksualitas secara berkala dari jenjang
SD sampai SMA. Sebab ia baru menyadari kalau ibunya kurang memberikan
pendidikan seksualitas ini. Ia menduga karena ibunya sendiri pun merasa aneh dan
tidak biasa membicarakan hal ini saat bersama ibunya dahulu.
Menurut Retha, nilai-nilai yang ditanamkan ibunya ini dilakukan melalui
berbagai peristiwa hidup yang relevan. Namun tidak ada waktu khusus seperti
duduk bersama di meja makan untuk membicarakan hal-hal seperti ini. Sedangkan
menurut Ibu Lely apa yang ia lakukan merupakan suatu proses kehidupan yang
mengalir dan dijalani saja.
64
Berjalan begitu aja ya...Nggak pake nyontek dari siapa-siapa
sih...memang hukum alamnya kayak gitu kali ya...ya memang
kenyataannya kayak begitu.
IV.B.1.6. Pengalaman Ibu dan Anak Perempuan dengan Identitas Ke-
Tionghoa-an
Seiring dengan pertumbuhkembangannya sebagai perempuan, Ibu Lely
merasakan bagaimana hidup dengan identitas ke-Tionghoa-an. Pada awalnya Ibu
Lely bersekolah di sekolah Cina di daerah Jatinegara. Namun ketika terjadi
peristiwa G30S saat ia kelas 1 SD, Ibu Lely berhenti sekolah. Pada masa itu yang
masih ia ingat setiap sore ibunya akan mengikatkan kunci ke baju singletnya
setiap sore sehabis mandi. Sampai hari ini ia tidak tahu kunci apa yang diikatkan
pada bajunya. Kedua orang tuanya juga membakar buku-buku yang bergambar
Mao Ze Dong.
Sejak kecil ia merasa sebagai warga minoritas di mana identitas ke-
Tionghoa-an selalu melekat dengan dirinya. Ia berupaya untuk menjadi sama,
tetap saja pada kenyataannya tetap terjadi pembedaan. Hal ini ia rasakan sejak
kecil dalam lingkungan pergaulan dan masyarakat di mana ia berinteraksi.
Dulu, ketika Ibu Lely lewat di jalan ia sering sekali dikatai dengan sebutan
“Amoy”. Ia merasa sangat tidak nyaman dengan sebutan ini. Ia pun merasa
adanya tiga nama yang ia miliki membuatnya sudah dijauhi orang dari awal. Oleh
karena itu, ia berpikir dengan adanya pergantian nama ia dapat lebih diterima di
masyarakat. Namun ternyata setelah pergantian nama dan naturalisasi
kewarganegaraan pun nama marga Tionghoa-nya tetap diperlukan dalam setiap
65
pengurusan surat kewarganegaraan. Sementara untuk menghilangkan nama marga
dari surat-surat kewarganegaraan ini perlu mengurus ke departemen kehakiman.
Akhirnya Ibu Lely tetap menggunakan nama marga ini pada surat-surat
kewarganegaraan.
Sampai hari ini pun, Ibu Lely masih merasakan perbedaan perlakuan
karena identitas ke-Tionghoaan-nya. Ia merasa tidak nyaman jika menggunakan
angkutan umum di daerah dekat rumahnya di mana ia satu-satunya keturunan
Tionghoa yang ada di dalam angkot. Kondisinya sangat berbeda ia alami jika
menggunakan angkutan umum di daerah Daan Mogot dan sekitar Jakarta Barat
dekat kantornya. Di sini ia banyak menemukan orang keturunan Tionghoa yang
sama-sama menggunakan angkutan umum. Ia merasa lebih aman, nyaman dan
merasa memiliki teman.
Ia juga tidak nyaman jika harus berbelanja di supermarket dekat
rumahnya. Sebab jika ia masuk ke dalam supermarket ini, ia merasa dilihat
sebagai orang yang aneh dari atas sampai bawah oleh orang lain. Ia sendiri merasa
bahwa orang-orang melihat dirinya sebagai orang aneh berkulit putih dan bermata
sipit mau berbelanja ke supermarket itu. Ibu Retha mengatakan bahwa ia lebih
menikmati dan merasa nyaman berbelanja di Pasar Baru atau Glodok. Sebab di
dua tempat ini, keturunan Tionghoa bukanlah minoritas.
Secara spesifik pembedaan karena identitas Tionghoa ini ia alami sewaktu
peristiwa Kerusuhan Mei’98 dan dalam kepanitian Paskah bulan April 2012 yang
lalu.
66
Saya tuh temen-temen di kantor juga mayoritas orang Indonesia. Malah
waktu saya di proyek, dari karyawan yang sekitar dua ribuan saya tuh
Cina sendiri dan Kristen sendiri. Saya sih selama ini nggak pernah
merasa berbeda sama mereka, Cuma saya sedikit merasa nggak nyaman
dengan mereka pas waktu kerusuhan. Itu di kantor saya kan di pasang
parabola, karena salah satu fasiltasnya kan antena parabola. Kalo di
Indonesia sendiri kan banyak yang disortir, kalo di CNN kan apa
adanya...di situ saya baru menyadari bahwa ternyata keseharian kita yang
udah hampir sepuluh tahun selama ini kita nggak pernah merasa berbeda,
nggak tau ya kalo mereka...saya sih ngerasa nggak beda. Mereka bisa
ngomong “Rasain tuh Cina, Dasar Cina”, Buat saya nggak nyaman, tapi
saya jadi tau oh itu toh isi perut mereka, yang mereka selama ini pikirin
seperti itu. Cuma karena selama ini saya atasan mereka jadi mereka
nggak berani. Jadi dia ngomong, dia nggak sadar kalo saya Cina, krn kita
sama-sama nonton tivi juga. Nah dia ga sadar kalo yang dikatain Cina-
cina itu, saya termasuk bagian di dalamnya. Saya rasa sampe saat ini dia
nggak pernah sadar kalo secara nggak langsung dia melukai hati orang.
Pada kepanitian Paskah April 2012 lalu di antara para panitia yang sedang
mempersiapkan acara dan sempat bersitegang, keluar umpatan “Dasar Cina” di
dalam rapat. Umpatan ini ditujukan pada Ibu Lely selaku bendahara dan ketua
panitia yang juga merupakan keturunan Tionghoa. Ibu Lely sebenarnya merasa
tidak nyaman dengan peristiwa ini. Namun ia tidak mau memperpanjang masalah
sehingga ia menganggapnya sebagai angin lalu saja.
Sementara Retha merasa pada generasinya sekarang ini ia merasa sudah
lebih bisa berbaur dengan yang lainnya.
...generasi kita sebenernya kan udah ngeblend, kalo generasi sebelumnya
kan masih. Jadi kalo sekarang, aku nggak gitu merasa berbeda.
Retha masih mengalami beberapa peristiwa di mana identitas ke-Tionghoa-annya
menjadi bahan ledekan oleh temannya. Pada masa sekolah, teman yang
meledeknya ini justru adalah orang Tionghoa juga. Sementara dalam kehidupan
67
perkuliahan, ledekan menggunakan identitas ke-Tionghoa-an muncul dalam
stereotipe yang juga digunakan untuk suku-suku lain. Namun ia memaklumi ini
sebagai bagian dari dinamika perkembangan dewasa muda.
Santai-santai aja denger temen diomongin gitu. Anak muda kan becanda-
becanda aja. Soalnya mereka nggak cuma ke Cina doang sih, kalo
misalkan suka ngomongin orang di belakang, ah biasa Jawa...gitu...jadi
lebih buat becanda...kalo yang ngomongnya keras, biasa Batak.
Jadi...yaudah..
Retha merasa dari keluarga terutama oleh ibunya ditanamkan identitas ke-
Tionghoa-an ini. Retha menilai hal ini sebagai suatu hal yang baik sebab
menurutnya seorang manusia itu harus memiliki akar. Ia merasa kesadaran dan
penanaman akan akarnya ini membantunya pada masa SMP-SMA ketika proses
pencarian jati diri.
Kayak...kan banyak orang Chinese yang tinggal di Indonesia yang
akhirnya malu kalau dia Chinese, soalnya banyak kan yang “ah lu
Cina...lu Cina” gitu kan...kalo aku nggak. Karena aku proud jadi
Chinese...karena memang dididik sama mama ee...dikasih tau gitu makna-
maknanya apa, ini tuh bagus...
IV.B.2. Subyek Kedua
IV.B.2.1. Latar Belakang Ibu Subyek Kedua
Ibu Olga merupakan anak ke-5 dari enam bersaudara keluarga Tionghoa
bermarga Gouw generasi kedua di Indonesia dari garis ayahnya. Ia menghabiskan
masa kecil di daerah Tanah Abang. Sehari-hari orang tuanya berjualan sayur dan
makanan matang di pasar dekat rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap
hari kehidupan di keluarga Ibu Olga berjalan begitu sibuk dan padat.
68
Setiap hari kedua orang tua Ibu Olga bangun pukul dua pagi untuk mulai
memasak dan menyiapkan berbagai kebutuhan untuk berjualan. Sementara Ibu
Olga bangun pukul lima untuk menimba air, memasak, menyiapkan sarapan,
mencuci lalu pergi ke sekolah pada pukul 07.00. Sehabis pulang sekolah jam
12.00, ibu Olga ke pasar membantu orang tuanya atau membawa pulang alat-alat
masak yang sudah tidak dibutuhkan. Di rumah, ibu Olga mengerjakan berbagai
pekerjaan rumah untuk keperluan seluruh anggota keluarga. Ia melakukan
pekerjaan ini bersama dengan saudara perempuannya. Kakak dan adiknya yang
laki-laki diperbolehkan tidak membantu mengurus rumah. Kakaknya yang laki-
laki merupakan anak yang pintar di sekolah, sehingga ia diberikan kesempatan
untuk memakai waktunya untuk belajar. Sementara saudara-saudara lainnya yang
sekolahnya biasa saja mengerjakan pekerjaan rumah.
Menurut ibu Olga, di keluarga Tionghoa ditanamkan dan diharapkan
bahwa anak perempuan bisa melakukan pekerjaan rumah dan memasak. Sewaktu
kecil ia juga tidak diperkenankan bepergian ke luar rumah seperti anak muda di
zaman sekarang. Kegiatan di luar rumah hanyalah sekolah. Itu pun tidak ada les
atau kursus di luar jam sekolah. Di sisa waktu, ia melakukan berbagai pekerjaan
membereskan rumah.
Ibu Olga menilai ibunya sebagai sosok yang tegas dan keras. Ia tidak
diperkenankan bertanya apalagi membantah apa yang sudah diperintahkan oleh
ibunya. Pada masa kecilnya, ibunya dapat menentukan dengan siapa ia boleh
berteman. Bahkan jika ibunya tidak menyukai temannya atau menilai teman ibu
69
Olga yang bertandang ke rumah tidak sopan, maka ibunya dapat mengusir teman
ibu Olga dari rumah mereka.
Ibu Olga merasa rutinitas kehidupan yang sibuk setiap harinya
menyebabkan tidak adanya waktu untuk bercengkrama dengan kedua orang
tuanya. Semua berjalan begitu saja seperti mesin yang terus bergerak setiap
harinya. Oleh karena itu, proses pendidikan yang ia alami di rumah sebagian besar
bersumber dari pengamatan terhadap apa yang dilakukan oleh kedua orang
tuanya.
Sosok ayah digambarkan ibu Olga sebagai orang tua yang keras dan jarang
berinteraksi dengan anak. Ada masanya di mana ayah dari ibu Olga menghabiskan
waktu dengan mabuk-mabukan dan berjudi sementara ibunya membanting tulang
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Ibu Olga merasa ia tidak memiliki privasi di dalam rumah. Hal ini juga
yang menyebabkannya memiliki keinginan untuk segera keluar dari rumah. Salah
satu jalan untuk keluar dari rumah menurut ibu Olga adalah dengan menikah
muda. Walaupun demikian, Ibu Olga merasa kesempatan untuk berkenalan dan
berinteraksi dengan teman dekatnya tidak sebebas zaman sekarang. Dulu ketika
pacarnya datang ke rumah, kedua orang tuanya ikut menemani di ruang tengah.
Bahkan ikut terlibat dengan pembicaraan mereka.
Ibu Olga berkenalan dengan suaminya dari teman mainnya. Suami ibu
Olga adalah kakak laki-laki dari teman main ibu Olga. Walaupun demikian,
hubungan ibu Olga dengan suaminya pada awalnya tidak disetujui oleh kedua
70
orang tuanya. Namun Ibu Olga merasa ia adalah orang yang berpendirian teguh
sehingga apa yang ia inginkan harus ia dapatkan. Ketika akhirnya ia direstui untuk
menikah, kedua orang tua ibu Olga mengatakan bahwa mereka tidak memiliki
uang sehingga kalau mau menikah ia harus mengusahakan sendiri. Pada masa itu,
di kalangan keluarga Tionghoa di lingkungan ibu Olga beredar anggapan bahwa
lebih penting menyelenggarakan pesta pernikahan dengan meriah daripada
mengurus surat-surat pernikahan. Biasanya mereka lebih malu pada tetangga jika
tidak membuat pesta yang meriah daripada khawatir tidak memiliki surat-surat
nikah. Namun ibu Olga berpendapat lain.
Menurut ibu Olga lebih penting membuat surat nikah daripada membuat
pesta pernikahan. Maka ibu Olga pun menikah dengan sederhana saja yang
penting surat-surat nikahnya jelas. Setelah menikah, ibu Olga tinggal di rumah
kontrakan bersama dengan suaminya. Pada umur 22 tahun, ibu Olga melahirkan
anaknya yang pertama.
Ibu Olga merasa tidak kesulitan memiliki anak di usia muda. Sebab dari
umur lima belas tahun ia sering mengurus anak dari kakak perempuannya yang
dititipkan di rumah ibunya. Kemudian tiga tahun berikutnya anak kedua lahir pada
tahun 1991 dan anak ketiga lahir pada tahun 1996.
Ibu Olga merasakan manfaat dari kehidupannya yang keras dan padat di
masa kecil ketika ia bekerja. Ia terbiasa hidup dengan jadwal dan rencana yang
rinci. Tujuh tahun pertama dalam pernikahannya ibu Olga bekerja sebagai
karyawan di perusahaan travel. Namun waktu yang tidak fleksibel dan jadwal
71
yang ketat sementara anak-anaknya masih kecil membuat ibu Olga berkeinginan
membuka usaha sendiri. Akhirnya ibu Olga bersama dengan suaminya mulai
membuka usaha sendiri yang terus berkembang dan dijalani sampai hari ini.
Saat ini kehidupan keluarga ibu Olga sangat mapan dan berkecukupan. Ia
dapat menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri dan selalu berlibur ke luar
negeri setiap liburan, disertai dengan aset-aset kepemilikan dan investasi yang
besar.
IV.B.2.2. Latar Belakang Anak Subyek Kedua
Shinta merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Ia mempunya dua
adik yang terpaut tiga dan tujuh setengah tahun. Ia menghabiskan masa kecilnya
tinggal di daerah Bekasi dan sejak SMP keluarganya bermukim di Kelapa Gading.
Selepas SMA, Shinta kuliah di Melbourne, Australia mengambil jurusal financial
accounting. Saat ini ia kembali ke Jakarta untuk bekerja dan membantu usaha
yang dirintis oleh kedua orang tuanya.
Shinta merasa ibunya jauh lebih keras mendidiknya saat ia masih kecil.
Tak jarang ia dipukul dan dikunci oleh ibunya di dalam kamar gelap jika ia
membantah. Namun beranjak dewasa ibunya semakin menempatkan dirinya
sebagai teman diskusi yang setara. Walaupun demikian ada keputusan-keputusan
hidupnya yang masih didominasi oleh ibunya. Salah satunya adalah
kepulangannya ke Jakarta untuk membantu usaha keluarga. Shinta sebenarnya
merasa lebih nyaman bekerja dan tinggal di Melbourne namun ibunya
menyuruhnya pulang untuk belajar mengurus usaha keluarga.
72
Setelah proses pertimbangan beberapa bulan, akhirnya ia menyetujui
keinginan ibunya untuk pulang kembali ke Jakarta. Shinta mengalami proses
penyesuaian yang tidak mudah saat kembali ke Jakarta. Bahkan sepanjang
pengambilan data pada bulan Maret 2012, isu ini sering ia utarakan. Ia merasa ada
kebebasan lebih yang bisa ia rasakan ketika tinggal sendiri. Selain itu kehidupan
di Melbourne menurutnya lebih teratur dan terprediksi daripada di Jakarta. Di
pihak lain, ia merasa bertanggung jawab juga untuk mengurus usaha keluarga
yang telah dirintis orang tuanya dan menghidupi keluarganya hingga hari ini.
IV.B.2. 3. Pengalaman Ibu sebagai Anak Perempuan di Keluarga Tionghoa
Ibu Olga menjalani rutinitas keseharian yang padat dari pukul lima pagi
sampai malam hari untuk bersekolah, membantu orang tua dan mengurus rumah.
Interaksi sehari-hari dengan orang tuanya terbilang minim karena orang tua lebih
fokus untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
“Sebetulnya mama tuh hampir nggak ngurus anak karena kita tuh
dikenain aturan, yang besar harus ngerawat yang kecil...Tapi kita belum
sempet besar pun udah bisa ngurus diri sendiri. Jadi sebenernya orang
tua lebih konsentrasi untuk cari uang, untuk uang sekolah, untuk
menghidupi anak-anaknya, untuk kasih kita.
Momen duduk bersama dengan orang tua pun hampir tidak ada. Sebab
semua sibuk menjalankan tugas masing-masing demi tercukupinya kebutuhan
rumah tangga.
Nggak pernah...kita hampir nggak pernah duduk berbicara. Karena
ee...masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri, trus orang tua
saya kalo malem pulang mereka sudah lelah, karena mereka kan kerjanya
lebih berat dari kita. Kita kan bangun jam lima, tapi orang tua jam dua
jam tiga, mereka udah bangun. Gitu...
73
Berbagai hal dipelajari ibu Olga dengan melihat bagaimana orang tuanya
berperilaku. Menurutnya orang zaman dulu dapat membuat anak melakukan apa
yang harus dilakukan tanpa banyak berdialog atau berdiskusi dengan anak. Tanpa
perlu diberitahu secara eksplisit, ibu Olga menyadari perannya sebagai anak
perempuan di dalam keluarga.
Jadi kalo perempuan di keluarga Tionghoa yang jelas tuh harus bisa
pekerjaan rumah, harus bisa masak. Ee...nggak boleh banyak pergi-pergi
kayak sekarang.
Ibu Olga tidak memiliki banyak waktu luang untuk dirinya sendiri. Setelah
pulang sekolah, ia harus segera pulang untuk menyelesaikan semua keperluan
rumah tangga dan hal-hal lain yang perlu dikerjakannya. Namun ia merasa
kehidupan seperti ini bukanlah suatu beban baginya. Sebab pada masa kecilnya, ia
merasa semua orang juga mengalami hal yang sama seperti dirinya. Selain itu,
tidak banyak kegiatan di luar rumah yang dapat dilakukan pada masa itu. Dengan
demikian, mengerjakan pekerjaan rumah tangga menjadi kegiatan keseharian ibu
Olga selain bersekolah.
Kondisi keuangan keluarga yang terbatas juga membuat ibu Olga tidak
dapat sering pergi berekreasi bersama keluarga. Bahkan ia tidak diberikan uang
saku sehari-hari oleh orang tuanya sehingga setiap hari ia selalu berjalan kaki dari
rumah ke sekolah sebab tidak memiliki uang untuk menggunakan kendaraan
umum. Pengalaman hidupnya membuat ibu Olga menyadari tugasnya sebagai
anak adalah menuruti perintah orang tua sehingga kehidupannya bisa lebih baik
dari orang tua.
74
Kita cuma punya tugas, apa yang ditugasin sama orang tua di rumah,
sekolah yang baik, udah...pulang ke rumah, cari jodoh yang baik supaya
kehidupan bisa lebih maju ke depannya.
Komunikasi yang minim dengan orang tua, membuat ibu Olga tidak
memiliki ruang untuk mengeluarkan pendapat maupun perasaannya. Apapun yang
dikatakan orang tua harus dituruti dan diterima tanpa ada kesempatan untuk
bertanya apalagi memprotes.
Kalo dulu, kita nggak boleh terbuka... Terus, banyak hal yang tabu.
Ee...apa namanya, kalo ngomong sama orang tua juga mesti diatur
omongannya. Trus, nggak boleh argue...Ya kalo orang tua bilang item ya
harus item...Kita nggak boleh nanya, kenapa harus item? Kenapa harus
putih? Nggak boleh...pokoknya kalo orang tua bilang A, ya A. Semua
harus A.
Pada interaksi di dalam keluarga, ibu Olga juga merasakan perbedaan
perlakuan antara dirinya dengan kakak laki-laki tertuanya yang berprestasi di
sekolah. Kakak laki-lakinya yang dinilai pintar dalam pelajaran di sekolah
diberikan keistimewaan untuk menggunakan waktunya hanya untuk belajar.
Sementara adik-adiknya yang biasa saja dalam pelajaran diharuskan tetap
mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ibu Olga menilai hal ini sebagai perbedaan
perlakuan karena tingkat intelegensi, bukan karena perbedaan gender,
Nah, ada kakak saya tuh yang satu, sangat pandai. Sekolahnya bagus, jadi
dia diistimewakan di rumah. Dia boleh nggak kerja. Dia boleh belajar
terus, sedangkan kita yang lainnya, yang sekolahnya biasa-biasa harus
meng-cover. Jadi yang sekolahnya biasa tuh punya beban yang lebih
berat dari yang sekolahnya luar biasa.
Secara garis besar, rutinitas hidup ibu Olga setiap harinya dari hari Senin
sampai Jum’at memiliki ritme yang sudah terprogram dan sistematis. Ia juga
75
mengupayakan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan. Sebab jika ia terlambat, maka kegiatan berikutnya dapat terhambat.
...jam lima pagi, bangun masak air, bantu-bantu bawa sayur ke pasar,
deket kan sama rumah...trus balik ke rumah, mandi, berangkat
sekolah...Pulang sekolah kan harus langsung. Dulu sekolah ga kayak
jaman sekarang, pulang jam dua-jam tiga ya. Dulu jam dua belasan udah
pulang. Jam dua belas pulang sekolah, balik lagi ke pasar, ke tempat
orang tua saya dagang, saya bantuin lagi ngangkat barang, ee...nyuci,
ngepel, gitu...
Di malam minggu dan di hari Minggu, ibu Olga tetap bekerja membantu
orang tuanya. Bahkan di hari libur pekerjaannya jauh lebih berat sebab seluruh
waktu dihabiskan untuk membantu orang tua dan mengurus rumah.
Biarpun hari Minggu, saya nggak boleh punya ekstra bangun siang. Jam
lima harus jam lima, tetep. Malam minggu lebih berat karena nggak
sekolah kan. Jadi sepanjang hari bantu di tempat dagang.
Kebiasaan ibu Olga membantu orang tua ini membuatnya sejak kecil
sudah mahir memasak, membuat sambal dan mengurus rumah tangga. Selain itu,
ia juga sudah terbiasa melakukan tugas berat untuk anak seusianya seperti
mencuci kain lap yang terkena minyak babi dan sangat lengket, menjemur kulit
babi di atas genteng untuk dijadikan kerupuk, menggoreng kulit babi di atas wajan
panas dan menimba air untuk seluruh anggota keluarga. Menurut ibu Olga,
hampir semua pekerjaan kasar sudah pernah ia lakukan semasa kecilnya.
IV.B.2.4. Kesadaran akan Adanya Perubahan Nilai-nilai yang
Disosialisasikan
76
Ibu Olga menyadari perubahan nilai-nilai yang disosialisasikan pada
keluarga intinya saat ini. Perubahan-perubahan tersebut berasal dari
ketidakpuasannya sebagai anak di keluarganya terdahulu. Maka ketika
membangun keluarga sendiri ia berusaha memberikan keterbukaan dan kebebasan
yang dahulu ia rindukan.
Ya...pokoknya gini...ee...pasti kita ngedidik anak dari pengalaman kita,
tapi saya banyak mengambil hikmah, mana yang menurut saya tidak baik
dulu waktu pengalaman saya masih kecil, itu saya rubah.
Misalnya...seperti nggak pernah ngobrol sama anak, enggak. Saya sangat
deket sama anak-anak. Kita bisa becanda, kita bisa ngobrol apa-
apa...ngomong yang porno-porno bebas di sini. Ee...karena, dari dulu
saya punya prinsip semakin dilarang, semakin bikin orang penasaran.
Jadi saya membebaskan. Sampe yang menurut orang paling harus
dilarang, nggak saya larang. Ee...sampe sekarang pun saya menerapkan
hal itu.
Ibu Olga juga menyadari bahwa dulu ia tidak dekat dengan orang tuanya.
Menurutnya, hal ini dikarenakan kehidupan yang begitu sibuk dan keras sehingga
orang tuanya terfokus pada usaha untuk menghidupi keluarga. Oleh karena itu ibu
Olga berupaya agar di dalam keluarganya sekarang ia dapat menjalin kedekatan
dengan anak-anaknya melalui obrolan.
Entah di dalam hati mereka apa saya nggak pernah tau, tapi mungkin juga
ada penyesalan kan karena nggak pernah bisa deket sama anak, nggak
pernah punya waktu banyak duduk sama kita, mungkin kan...Jadi tuh semua
hal saya terapkan di dalam hidup saya yang sekarang...kita lebih deket,
segala hal bisa diskusi, sampe kita bisa ngomongin cowo gimana di
rumah...temen yang manapun boleh dateng...
Ibu Olga juga berupaya melakukan usaha preventif jika anak perempuannya
sampai hamil di luar nikah. Ia ingin agar anak-anaknya memberikan kepercayaan
terbesar kepada orang tua dan berusaha bersama-sama untuk mencari jalan keluar.
77
Bukan dengan bunuh diri, aborsi atau jalan keluar lain yang tanpa disertai
pemikiran matang.
...pada umumnya...saya membebaskan mereka untuk bicara untuk
melakukan apa pun, untuk membuat keputusan apa pun. Meskipun sampai
hal mengenai, kalau mereka punya anak di luar nikah bagaimana itu saya
udah diskusiin. Kebetulan anak saya tiga, perempuan. Jadi saya
mengatakan kepada mereka, bahwa kalaupun hal itu terjadi, orang yang
pertama kali harus kamu kasitahu adalah mama. Dan jangan kamu
merasa bahwa itu adalah suatu hal yang memalukan. Malu apa nggak itu
urusan kita. Yang jelas tuh nggak boleh melakukan satu tindakan bodoh,
misalnya aborsi atau bunuh diri.
Ibu Olga menginginkan anak-anaknya tidak memikirkan bagaimana pendapat
orang. Sebab ia ingin dapat menjadi partner bagi anak-anaknya untuk membantu
mereka menangani masalahnya.
Kalau mereka salah jalan, yang paling pertama musti menolong mereka,
menurut saya tuh kita. Jangan sampe karena kata-kata kita yang “jangan
sampe mencoreng, jangan sampe ini...” membuat mereka tuh nggak mau
ngomong, takut kan mencoreng...jadi bunuh diri, jadi aborsi itu saya
hindari. Jadi saya kasitau anak-anak no problem. Jadi jangan pikirin
bagaimana omongan orang, bagaimana omongan tetangga, jangan
peduli. Pokoknya kalau udah melakukan kesalahan, yaudah...kita sama-
sama betulin mesti gimana...gitu.
Walaupun demikian, Ibu Olga juga menyadari bahwa anak-anaknya tidak akan
bisa menjadi pribadi yang sekuat Ibu Olga. Ia sering merasa terlalu memanjakan
anak-anaknya dengan kehidupan yang terlalu nyaman.
Ee..saya lebih banyak bercerita sama mereka tentang kehidupan saya dulu
dan mengatakan bahwa kehidupan mereka jauh lebih baik, tapi kadang
saya merasa gagal mendidik anak karena saya merasa mereka tidak akan
bisa jadi seperti saya. Ee...orang kan nggak bisa sama, tapi saya mau
mereka bisa menerapkan falsafah hidup saya. Tapi saya merasa mereka
nggak bisa seperti itu karena saya udah membuat mereka hidup nyaman
78
dari kecil. Jadi saya yakin pasti mereka tidak akan bisa seperti saya,
karena saya salah mendidik.
Sewaktu anak-anaknya kecil, Ibu Olga tidak mengizinkan mereka memasak atau
menyeterika sebagaimana dulu ia melakukan aktivitas-aktivitas ini sejak usia dini.
Di masa sekarang, Ibu Olga berusaha menebus “kesalahannya” dengan mengajak
anaknya bekerja bersamanya. Diharapkan anak-anak Ibu Olga dapat mencontoh
bagaimana Ibu Olga menghadapi hidup sehari-hari.
Cuma saya berusaha memperbaiki kesalahan saya dengan cara mereka
bekerja di dekat saya, dan mereka melihat bagaimana saya menghandle
semua, bagaimana saya menghadapi masalah, bagaimana saya nepatin
janji ke orang, bagaimana berkomitmen, itu cara yang saya lakukan..
Shinta membenarkan bahwa ibunya sering menceritakan bagaimana pengalaman
hidupnya dahulu. Bahkan pengalaman hidup ibunya mempengaruhi keputusan
Shinta untuk melanjutkan sekolah.
Iya, dia sering banget kok nyeritain tentang pengalaman hidupnya, dulu
Oma bagaimana gitu...galak...Contohnya, dulu waktu aku kuliah, dulu tuh
selesai SMA tuh, aku ada pikiran kalo aku tuh nggak mau kuliah, mau
kerja aja...Cuma mama bilang, jaman dulu dia tuh pengen banget
kuliah...tapi nggak ada uangnya, nggak ada biaya. Sekarang bisa
nyekolahin anak, kenapa nggak gitu...pokoknya harus...karena ada
biayanya, harus sekolah...Pokoknya kayak gitu... Kayak dulu nggak bisa,
sekarang bisa, makanya dikerjain...Kesempatannya ada gitu...
Shinta mensyukuri kehidupannya di masa sekarang ini. Ia tidak bisa
membayangkan bagaimana hidup di zaman ibunya tanpa kemudahan hidup dan
kecanggihan teknologi seperti sekarang ini.
Kalo denger kayak gitu sih...selalu ngomong dalam hati, untung aku
nggak hidup di zaman yang itu... (tertawa). Kalo nggak, bisa gila...Jadi
kayak, bersyukur sih...kalo sekarang tuh nggak sesusah yang dulu,
79
sekarang nggak sekaku yang dulu. Jadi kayak segala tempat, mall gitu
lebih banyak...Kalo dulu kan, telpon aja nggak ada, hape nggak ada gitu.
Sekarang mikir, kalo nggak pake BB aja nih, gimana...kayak aneh...nggak
ada internet...jadi bersyukur...
IV.B.2.5. Sosialisasi Identitas Gender pada Anak Perempuan
Ibu Olga mendidik anak-anak perempuannya untuk memiliki sikap
menghormati, terutama pada yang lebih tua serta menjaga rasa kekeluargaan.
...cuma kalo yang saya tetep terapin adalah menghormati. Bagaimana
menghormati orang yang lebih tua dari kita. Bagaimana kita tetep
menjaga rasa kekeluargaan. Bagaimana yang muda ke yang tua harus
memanggil menurut tingkatannya. Soalnya, pada saat dia panggil orang
dengan tingkatannya, tidak dengan nama, itu secara tidak langsung
membuat orang tersebut sadar bahwa dia levelnya di mana.
Ibu Olga juga berusaha mengajarkan dan menanamkan nilai kerja keras
pada anak-anaknya dengan menceritakan kisah hidupnya yang penuh perjuangan
pada anak-anaknya. Hal ini dibenarkan oleh penuturan Shinta, anaknya.
Iya, dia sering banget kok nyeritain tentang pengalaman hidupnya, dulu
Oma bagaimana gitu...
Menurut ibu Olga dengan perubahan zaman dan kondisi, ia sangat yakin
bahwa anak-anaknya tidak akan sekuat dirinya. Oleh karena itu, ia merasa dengan
menceritakan kisah hidupnya, paling tidak anak-anaknya dapat mempelajari
falsafah hidupnya.
Namun bagi Shinta sendiri, ia merasa ada beban dan harapan lebih yang
diberikan padanya sebagai anak pertama di dalam keluarga. Sejak ia kecil, ia
selalu harus bertanggung jawab untuk kesalahan yang dilakukan oleh adiknya.
80
...aku sih ngerasanya karena anak pertama, rasanya tuh lebih beban...jadi
kayak dari dulu dari kecil, kalo misalnya adiknya kenapa gitu...padahal
bukan salah aku, tapi aku pasti diomelin...Katanya aku paling gede
gitu...jadi harus kasih contoh yang baik untuk adiknya, jadi adiknya nggak
seperti itu...gitu...jadi satu salah, semua kena...
Shinta merasa segala perilakunya harus menjadi contoh yang baik untuk
adik-adiknya. Menurutnya, ibu Olga sangat menekankan ini kepadanya.
...misalnya masalah pulang malem gitu, diomelin...dibilangnya itu bukan
contoh yang bener buat adiknya, pasti adiknya nanti ngikutin. Kalo nanti
dia udah gede, pasti dia nanya...kalo Cici boleh begitu, kenapa dia nggak.
Jadi dari dulu tuh ditanemin untuk jadi contoh yang baik untuk adiknya
karena anak paling besar.
Perlakuan seperti ini yang diterima Shinta sejak kecil lama kelamaan
membentuk proses berpikir, yang pada akhirnya mempengaruhi bagaimana Shinta
berperilaku. Ia terbiasa memikirkan dampak dari perilaku yang dilakukannya bagi
adik-adiknya.
Sampe sekarang sih masih terbebani gitu, cuma udah terbiasa...Jadi kayak
berjalannya waktu, udah jadi kebiasaan gitu...Setiap kali apa,
mikir...entar adiknya gimana yaa...harus gimana gitu... Jadi udah
terbiasa, apa ya...udah jadi kebiasaan idup aja gitu (tertawa).
Shinta merasa nilai kerja keras yang ditanamkan oleh ibunya merupakan bagian
dari nilai (value) yang dimiliki oleh orang Cina pada umumnya.
Aku rasa sih karena orang Cina, dari nenek moyangnya itu orangnya emang
pekerja keras dan konsisten...Kalo dari yang aku liat, menurut pandangan
aku, semua orang Cina itu pekerja keras...
Di saat ini Ibu Olga berusaha untuk memperlakukan anak secara setara. Hal ini
juga yang dirasakan oleh Shinta di mana ia merasa dapat berdiskusi dengan
ibunya. Termasuk memberi masukan mengenai cara berpakaian ibunya.
81
Begitu juga kita ke mama, Ih jangan pake itu sih ke mama, pake yang lain
lah yang lebih santai. Kayak saling kritik pakaiannya. Kalo misalnya mau
ke pesta, pake ini aja, pake ini aja. Walaupun tegas bisa juga jadi temen
yang seumuran.
Shinta menyadari hubungan yang setara dengan ibunya baru dirasakannya akhir-
akhir ini ketika semakin beranjak dewasa. Sementara pada waktu ia kecil, ibunya
tergolong tegas dalam mendisiplinkan anak. Terutama berkaitan dengan nilai
akademis di sekolah dan kepatuhan menjalani peraturan di rumah. Sosialisasi dan
pengkondisian seperti ini dari Ibu Olga terinternalisasi di dalam diri Shinta
sebagai nilai-nilai hidup yang membuatnya berusaha melakukan yang terbaik.
Karena mungkin...aku sendiri takut, tiap kali ambil raport, aduuh jangan
merah. Kalo merah, nggak tau nih diapain...takut digebukin gitu
(tertawa), takut diomelin...ntar bisa nggak boleh pergi jalan-
jalan...pokoknya jangan merah. Jadi kayak, mau nggak mau, berusaha
gitu supaya nilainya bagus...Supaya nantinya bisa seneng-seneng, jangan
sampe kayak haha hihi sekarang trus kalo nilainya jelek, ntar nggak bisa
berbuat apa-apa, nggak naik kelas lagi... belom lagi malunya kalo nggak
naik kelas...males lagi ngulang.
Shinta menyetujui pola hubungan seperti yang ia alami bersama ibunya. Anak
bisa berdiskusi dengan orang tua namun juga tetap hormat pada orang tua.
Aku sih setuju-setuju aja sih, nggak ada komplain.Menurut aku ada
saatnya orang tua bisa jadi temen, bisa ngomongin apa aja ya nggak
semuanya sih tapi bisa nggak takut mau cerita ke orang tua. Tapi dengan
mereka tegas, semacam ada boundaries, jadi kita tahu ada batasannya
walaupun dekat, nggak bisa kayak temen.
Shinta mengaku memiliki selera berpakaian yang sama dengan ibunya. Walaupun
demikian, Shinta tetap merasa adanya perbedaan antara dirinya dan ibunya
terutama dalam hal pemikiran. Menurut Shinta, ibunya sering mengkhawatirkan
82
hal-hal yang menurutnya tidak perlu dikhawatirkan. Salah satunya tentang masa
depan anak-anak perempuannya.
Yang sering bentrok sih masalah pemikiran aja...Mungkin karena aku
sempet sekolah di luar gitu. Kadang aku merasa mama suka worried hal-
hal yang seharusnya ga di-worried gitu...jadinya aku, yaudahlah...tapi
mama suka nggak terima. Tapi kalo hal-hal lain, nggak sih...jarang
berantem juga...Mama khawatirin...yah..gitulah...anak-anaknya...entar
bagaimana kalo misalnya udah kawin, kalo misalnya...pasangannya
jahat...atau ntar misalnya tinggal sendiri, kerja, nggak bisa menghasilkan
uang sendiri, yang susah, gitu-gitu lah...Kayak mama lebih khawatir kalo
nanti anaknya entar susah.
Menurut Shinta, kekhawatiran yang dimiliki Ibu Olga terhadap masa depan anak-
anaknya membentuk bagaimana perilaku Ibu Olga kepada anak-anaknya. Ibu
Olga menekankan pada ketiga anaknya untuk dapat hidup mandiri tanpa
bergantung pada orang lain.
Makanya mungkin dari dini, ditanemin ke anak-anaknya pokoknya kalo
apa-apa harus mandiri, bisa sendiri. Kayak kita nih, sebelum SMA,
sebelum umur 17 harus belajar nyetir, harus bisa naik mobil, jangan
bergantung sama supir. Jangan bergantung sama siapa-siapa, mungkin
karena cewek semua kali ya...mama khawatir...Jadi sebisa mungkin tuh
semua anaknya tidak bergantung sama orang lain. Jadi kalo misalnya
entar ditinggal sama orang lain, pasangannya, sama temennnya...itu
nggak yang gimana, masih bisa berdiri sendiri...
IV.B.2.6. Pengalaman Ibu dan Anak Perempuan dengan Identitas Ke-
Tionghoa-an
Ibu Olga dan Shinta memiliki pengalaman yang berbeda dalam hal identitas
ke-Tionghoan mereka. Ibu Olga pernah mengalami bersekolah di sekolah negeri
di tingkat sekolah dasar. Saat itu, ia satu-satunya keturunan Tionghoa di sekolah.
83
Bahkan di antara kakak dan adiknya, ibu Olga merupakan satu-satunya anak yang
pernah bersekolah di sekolah negeri.
Beliau mengakui pada awal mula masuk di sekolah negeri ia sering diledek
dan dilempari barang oleh teman-temanya. Namun hal ini tidak membuat Ibu
Olga gentar. Ia malah mendatangi teman yang melemparinya barang dan
mengajaknya untuk berkonfrontasi langsung. Lama-kelamaan teman-teman yang
sering meledeknya malah menjadi teman akrab Ibu Olga sampai sekarang.
Menurut Ibu Olga, sampai sekarang ia memiliki teman-teman akrab dari berbagai
latar belakang budaya dan suku.
Sementara Shinta merasa sebagai minoritas dengan identitas ke-
Tionghoaannya. Waktu di sekolah dasar, ia sempat bersekolah di sekolah Katolik
Strada yang mayoritas “pribumi”. Ia dan adiknya sering menjadi bahan ledekan.
Menurut Shinta ia merasa biasa saja diledek seperti itu. Namun ia merasa tidak
nyaman ketika diledek dengan sebutan “Mei Mei” saat berjalan di trotoar
sepulang mengikuti bimbingan belajar di SMAN 8.
Trus apalagi waktu SMA, aku kan sempet ikut les-lesan yang UMPTN, BTA
yang di SMA 8. Trus lagi jalan, trus ada abang-abang manggil...”Waah, Mei
Mei” yang ngatain Cina gitu...Sebenernya aku nggak seneng, tapi disautin
nggak perlu kan.
Di dalam pergaulan sehari-hari, Shinta merasa ibunya tidak memberikan batasan
atau larangan dalam berteman. Tetapi dalam memilih pasangan hidup, Ibu Olga
mewanti-wanti Shinta agar jangan mendapatkan pasangan yang beragama Islam.
Mama nggak pernah ngelarang aku untuk temenan sama siapa aja. Cuma
mungkin ya, emang dari sananya...setiap...bukan suku sih, tiap orang mungkin
84
kayak punya nggak suka yang sama ini... Mama cuma bilang dari dulu, kalo
berteman sama siapapun boleh. Cuma misalnya kalo mencari pasangan
hidup, mama ada nggak suka sama agama tertentu gitu. Jangan yang Islam
(suara mengecil). Mama cuma masalahin agama, tapi kalo yang lainnya
nggak pernah bilang, nggak boleh orang ini, nggak boleh orang itu.
Pengalaman Shinta berkuliah di Australia dan bertemu dengan teman-teman
sesama keturunan Cina dari Indonesia memberikannya perspektif lain. Dari cerita
teman-temannya ia mengetahui apa saja yang dialami teman-temannya saat
Kerusuhan Mei 1998. Sementara di saat itu, Shinta tidak mengalami apa-apa
karena ia tinggal di daerah Bekasi yang mayoritas adalah pribumi.
...waktu itu aku masih kelas 5 SD, jadi aku biasa aja, nggak ngerasa takut
atau apa. Lagian di komplek rumah juga nggak ada rusuh-rusuh kan,
tinggalnya di Bekasi. Temen-temen di Australi ada yang cerita gimana-
gimana, sampe ngumpet di loteng, balik ke Indo masih ada rasa trauma.
Tapi kalo aku sendiri nggak ada. Dia tinggal di daerah kota gitu, sampe
lari-lari ngumpet di loteng rumahnya. Abis itu dia kabur masuk ke gang-
gang, masuk ke rumah tetangga. Numpang duduk, nggak dikasih minum
atau apa...Cuma untuk sekedar numpang singgah. Denger kayak gitu sih
sedih...kenapa harus kayak gitu.
Ketika ditanya mengenai identitasnya, Shinta merasa ia berada di-antara (in
between) antara merasa sebagai orang Indonesia dan Australia.
Merasa in between, soalnya kalo bahasa Indonesia juga nggak bisa,
apalagi kalo nulis email resmi banyak yg ga tau bahasanya. Tapi kalo
dibilang kayak Australi, bahasa Inggrisnya juga nggak jago-jago amat.
Jadi bingung sih...in between. Kalo dibilang nggak suka Indonesia, tapi
aku hidup dan besar di sini. Kalo aku lebih suka tinggal di Australi tapi
sebenernya hidupnya juga nggak enak-enak amat di sana, mesti berjuang
juga.
Sementara Ibu Olga dapat dengan mantap dan yakin mengakui dirinya sebagai
orang Indonesia. Sebab ia lahir dan besar di Indonesia. Sampai mati pun akan
tetap menjadi orang Indonesia.
85
Merasa sebagai orang Indonesia karena saya tinggal di Indonesia, besar
di Indonesia, saya tau segala sesuatu tentang Indonesia dan akan
meninggal di sini. Jadi, saya orang Indonesia.
IV.C. Analisis Antar Subyek
IV.C.1. Latar Belakang Kehidupan Ibu
Pada tabel berikut ini, dapat dilihat gambaran latar belakang kehidupan Ibu Lely
dan Ibu Olga, beserta persamaan dan perbedaannya.
Tabel IV.C.1.1. Perbandingan Latar Belakang Kehidupan Ibu
Ibu Lely Ibu Olga
Latar Belakang
Keluarga
- Keluarga Tionghoa
generasi kedua di
Indonesia.
- Besar di daerah
Jatinegara, Jakarta
Timur
- Ayah berjualan beras
dan pedagang
kelontong. Sementara
ibu menjadi ibu
rumah tangga di
rumah.
- Anak ke-4 dari 10
bersaudara
- Keluarga Tionghoa
generasi ketiga di
Indonesia
- Besar di daerah
Tanah Abang, Jakarta
Pusat
- Ayah dan ibu
berjualan makanan
matang dan sayur-
sayuran di pasar.
- Anak ke-5 dari 6
bersaudara
Persamaan - Berasal dari keluarga Tionghoa yang besar di
Jakarta
- Mata pencaharian keluarga adalah berjualan
Perbedaan - Ibu dari Ibu Lely
adalah seorang ibu
rumah tangga.
- Ibu Lely dibesarkan
di Jatinegara yang
lebih kental
komunitas
Tionghoanya
- Ibu Lely lahir tahun
1958.
- Ibu dari Ibu Olga
berjualan sendiri,
terpisah dari usaha
suaminya
- Ibu Olga dibesarkan
di daerah Kebon
Kacang.
- Ibu Olga lahir tahun
1966
- Perbedaan tahun lahir ini berkontribusi pada
perbedaan pengalaman hidup mereka. Antara lain,
Ibu Lely masih mengalami bersekolah di sekolah
Cina. Sementara Ibu Olga yang lahir setelah
peristiwa G30S bersekolah di sekolah negeri
86
Kehidupan di dalam
keluarga
Ibu Lely
- Selesai sekolah harus
segera pulang ke
rumah untuk
membantu
mengerjakan urusan
rumah tangga dan
mengurus keluarga.
- Tidak diperkenankan
mengikuti kegiatan
lain di luar sekolah
- Ibu sangat kolot dan
kaku sementara Ayah
dinilai lebih sabar
dan baik. Apa yang
dikatakan dan
diperintahkan oleh
ibu tidak boleh
dibantah.
- Anak laki-laki di
dalam keluarga boleh
bermain dan tidak
membantu mengurus
pekerjaan rumah.
Sementara anak
perempuan
mengerjakan semua
urusan rumah tangga.
Ibu Olga
- Selesai sekolah harus
segera pulang ke
rumah untuk
membantu
mengerjakan urusan
rumah tangga dan
mengurus keluarga.
- Tidak diperkenankan
mengikuti kegiatan
lain di luar sekolah
- Jarang berinteraksi
bersama ayah dan
ibu. Namun menilai
Ibu sebagai orang
yang sangat keras.
Apa yang dikatakan
dan diperintahkan
oleh ibu tidak boleh
dibantah.
- Anak laki-laki di
dalam keluarga boleh
bermain dan tidak
membantu mengurus
pekerjaan rumah.
Sementara anak
perempuan
mengerjakan semua
urusan rumah tangga
Persamaan - Ibu Lely dan Ibu Olga diharuskan untuk segera
pulang ke rumah sesuai sekolah untuk membantu
mengerjakan urusan rumah tangga.
- Mereka tidak diperkenankan mengikuti kegiatan
lain di luar sekolah. Namun saudara laki-laki
mereka diperbolehkan untuk bermain di luar
rumah dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah.
- Orang tua Ibu Lely dan Ibu Olga
mengembangkan pola asuh otoriter pada anak-
anaknya. Terutama para ibu yang menegakkan
peraturan dan memberikan konsekuensi hukuman
pada anak-anak tanpa banyak kompromi dan
diskusi.
- Ibu Olga dan Ibu Lely merasa ibu mereka banyak
melarang mereka melakukan hal yang mereka
87
sukai, terutama yang berkaitan dengan kebebasan
berpendapat dan berkegiatan di luar rumah.
Perbedaan - Ibu Lely membantu
ayahnya berjualan
sebatas menunggui
toko kelontong milik
ayahnya.
- Ibu Lely memiliki
keinginan yang tinggi
untuk mengikuti
kegiatan
ekstrakurikuler
sekolah seperti
bermain Drum Band.
- Ibu Lely menyadari
perbedaan karakter
ibu dan ayahnya.
- Aktivitas Ibu Lely
mengurus kebutuhan
rumah tangga
terbatas pada
kegiatan
membersihkan rumah
dan berbelanja ke
pasar. Beliau baru
bisa memasak
menjelang menikah.
- Ibu Olga tak hanya
mengerjakan
pekerjaan rumah
tangga saja, tetapi
juga ikut menyiapkan
keperluan untuk
orang tuanya
berjualan.
- Ibu Olga merasa
tidak terlalu merana
karena harus berdiam
di rumah.
- Ibu Olga merasa
tidak banyak
berinteraksi dengan
orang tuanya karena
padatnya aktivitas
berjualan setiap hari
- Ibu Olga melakukan
semua pekerjaan
kasar di rumah.Sejak
kecil, Ibu Olga sudah
terbiasa memasak
untuk kebutuhan
rumah tangga dan
berjualan.
Pada tabel IV.C.1.1., terlihat persamaan dan perbedaan latar belakang
keluarga Ibu Lely dan Ibu Olga. Perbedaan latar belakang keluarga ini
membentuk keunikan masing-masing. Namun ketika Ibu Lely dan Ibu Olga
masuk ke tahap pernikahan, keduanya menjalankan peran sebagai istri dan ibu
yang hampir serupa. Usaha keduanya menjalankan peran sebagai istri dan ibu
sejalan dengan teori social-learning dan reproduksi peran ibu (Chodorow, 1978).
88
Hasil pengalaman dan pembelajaran diimplementasikan ketka mereka sendiri
sudah menjalani peran sebagai ibu secara aktif. Deskripsi ini dapat dilihat pada
tabel IV.C.1.2. berikut ini.
Tabel IV.C.1.2. Perbandingan Usia Menikah Ibu
Usia Pada Saat
Menikah
Ibu Lely
- 24 tahun Ibu Olga
- 21 tahun
Persamaan - Ibu Lely dan Ibu Olga menikah pada rentang usia
dewasa muda (early adulthood).
- Ibu Lely dan Ibu Olga menikah setelah memiliki
pengalaman bekerja selama 1-3 tahun
- Setelah menikah, Ibu Lely dan Ibu Olga berpisah
dari keluarganya dan tinggal di rumah kontrakan
bersama suaminya.
- Anak pertama lahir di tahun pertama pernikahan.
- Setelah menikah, Ibu Lely dan Ibu Olga tetap
bekerja sekaligus menjalankan peran sebagai istri
dan ibu rumah tangga.
- Walaupun bekerja, Ibu Lely dan Ibu Olga setiap
hari selalu memasak untuk keluarganya
Perbedaan - Ibu Lely menikah
dengan teman
gerejanya.
- Setelah menikah, Ibu
Lely masih sering
bertanya pada ibunya
mengenai cara
memasak makanan.
Ia juga melibatkan
ibunya dalam
pengasuhan anak
pertamanya.
- Ibu Olga menikah
dengan kakak dari
teman baiknya.
- Ibu Olga mengurus
anaknya sendiri.
Pada Tabel IV.C.1.3. terlihat perbedaan pendidikan akhir Ibu Lely dan Ibu Olga,
bukan hanya dari gelar akademis saja tapi juga perbedaan pandangan dan perilaku
mereka terhadap pendidikan akademis.
Tabel IV.C.1.3. Perbandingan Pendidikan Akhir Ibu
89
Pendidikan Akhir - D1 - SMK
Persamaan - Pendidikan Ibu Lely dan Ibu Olga sebelum
menikah adalah SMA
Perbedaan - Ibu Lely melanjutkan
pendidikan D1
setelah 12 tahun
menikah, yaitu pada
saat ia berhenti
bekerja dari
pekerjaan
sebelumnya. Ia
mengisi waktu
luangnya dengan
sekolah Bahasa dan
Sastra Mandarin.
- Ijazah D1 ini menjadi
sarana memenuhi
kebutuhan rumah
tangga dengan
menjadi guru les
bahasa Mandarin
selama 9 tahun.
- Ibu Olga walaupun
telah memiliki uang
untuk melanjutkan
sekolah, merasa
sudah tidak memiliki
waktu dan tenaga. Ia
merasa lebih baik ia
memfokuskan diri
untuk
menyekolahkan
anaknya. Ibu Olga
memendam
keinginan untuk
mengambil jurusan
Hukum.
IV.C.2. Pengalaman Ibu sebagai Anak Perempuan Keluarga Tionghoa
Kehidupan sebagai anak perempuan keluarga Tionghoa membentuk
dinamika internal Ibu Lely dan Ibu Olga sebagai individu, maupun ekspektasi
terhadap lingkungan sekitar mereka. Pada Tabel IV.C.2.1. dideskripsikan
perbandingan pengalaman masa kecil Ibu Lely dan Ibu Olga.
Tabel IV.C.2.1. Perbandingan Pengalaman Ibu sebagai Anak Perempuan
Keluarga Tionghoa
Ibu Lely Ibu Olga
- Bertugas membantu ibunya dalam
mengurus kebutuhan rumah tangga.
Mereka tidak punya pembantu
sehingga segala urusan rumah
tangga dikerjakan sendiri oleh ibu
dan anak-anak perempuan.
- Menghabiskan waktunya di luar
- Mengerjakan berbagai pekerjaan
rumah untuk keperluan seluruh
anggota keluarga. Ia melakukan
pekerjaan ini bersama dengan
saudara perempuannya
- Menurut ibu Olga, di keluarga
Tionghoa ditanamkan dan
90
waktu sekolah untuk mengerjakan
pekerjaan rumah. - Ia ingin sekali
bisa mengikuti aktivitas di luar
rumah seperti ekskul Drum Band
yang diadakan sekolahnya setiap
hari Minggu. Namun karena
kegiatan ini dilakukan di luar jam
sekolah maka Ibu Lely tidak dapat
mengikutinya.
- Merasa ibunya sebagai orang tua
yang kolot, galak dan cerewet serta
tidak pandai bergaul. Ibu Lely
merasa ibunya banyak mengatur
dan mengekang serta terlalu banyak
melarang.
- Kebebasan sebagai anak
perempuan jarang ia rasakan.
Sementara ia melihat sendiri
bagaimana saudara laki-lakinya
diperbolehkan bermain dengan
bebas dan tidak dibebankan tugas
membersihkan rumah seperti anak-
anak perempuan.
- Ibu Lely sangat senang bersekolah.
Sebenarnya ia ingin bersekolah
tinggi. Namun ketiadaan biaya
membuatnya harus mengurungkan
niatnya ini. Selepas SMA Ibu Lely
tahu bahwa ia tidak mungkin
melanjutkan sekolah dan harus
bekerja
- Ibu Lely merasakan manfaat dari
didikan ibunya yang keras dan
disiplin setelah ia menikah dan
memiliki anak.
diharapkan bahwa anak perempuan
bisa melakukan pekerjaan rumah
dan memasak.
- Sewaktu kecil tidak diperkenankan
bepergian ke luar rumah seperti
anak muda di zaman sekarang.
Kegiatan di luar rumah hanyalah
sekolah. Itu pun tidak ada les atau
kursus di luar jam sekolah. Di sisa
waktu, ia melakukan berbagai
pekerjaan membereskan rumah.
- Ibu Olga menilai ibunya sebagai
sosok yang tegas dan keras. Ia tidak
diperkenankan bertanya apalagi
membantah apa yang sudah
diperintahkan oleh ibunya.
- Ibu Olga merasa rutinitas kehidupan
yang sibuk setiap harinya
menyebabkan tidak adanya waktu
untuk bercengkrama dengan kedua
orang tuanya.
- Ibu Olga merasa ia tidak memiliki
privasi di dalam rumah. Hal ini juga
yang menyebabkannya memiliki
keinginan untuk segera keluar dari
rumah. Salah satu jalan untuk
keluar dari rumah menurut ibu Olga
adalah dengan menikah muda.
- Ibu Olga memiliki cita-cita untuk
berkuliah di fakultas hukum.
Namun akhirnya ia hanya
bersekolah sampai SMK agar dapat
langsung bekerja.
- Ibu Olga merasakan manfaat dari
kehidupannya yang keras dan padat
di masa kecil ketika ia bekerja. Ia
terbiasa hidup dengan terjadwal dan
rencana yang rinci.
Dari perbandingan tabel, secara umum terlihat kehidupan yang dialami Ibu
Lely dan Ibu Olga sebagai anak perempuan keluarga Tionghoa banyak
91
dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga yang terbatas. Maka sebagai bagian
dari anggota keluarga Ibu Lely dan Ibu Olga ikut membantu menopang kehidupan
keluarga dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, maupun berjualan.
Menurut Kim (2003), keluarga Tionghoa yang berlandaskan ajaran
Konfusius menjunjung tinggi sikap berbakti dan hormat anak kepada keluarga dan
orang tua sekalipun harus mengorbankan impian dan ambisi diri sendiri. Terlihat
bagaimana Ibu Lely dan Ibu Olga diharapkan dan diajarkan sebagai anak
perempuan keluarga Tionghoa untuk memenuhi ekspektasi dan tuntutan keluarga.
Seringkali ekspektasi keluarga tidak sesuai dengan keinginan mereka sendiri.
Meij (2009) mengatakan anak-anak di keluarga Tionghoa memiliki nilai
penghormatan yang tinggi terhadap orang tuanya. Tak heran muncul perilaku
mendahulukan dan mematuhi keinginan orang tua dibandingkan keinginan diri
sendiri.
Ibu Lely dan Ibu Olga tetap berusaha mematuhi dan menjalankan apa yang
diinginkan oleh keluarganya. Namun di dalam diri mereka, terjadi proses refleksi
dan internalisasi yang memunculkan kesadaran adanya perbedaan antara
ekspektasi keluarga dengan keinginan pribadi. Hal inilah yang memunculkan
perbedaan sosialisasi identitas gender ketika Ibu Lely dan Ibu Olga menjadi ibu
bagi anak-anak perempuannya.
IV.C.3. Kesadaran akan Adanya Perubahan Nilai-nilai yang Disosialisasikan
Pada tabel IV.C.3.1. dapat dilihat perbandingan kesadaran akan perubahan
nilai-nilai yang disosialisasikan Ibu Lely dan Ibu Olga kepada anak-anak
92
perempuannya. Perubahan ini muncul dari pengalaman diri Ibu Lely dan Ibu Olga
yang dimodifikasi sehingga sesuai dengan apa yang mereka harapkan namun tidak
dapat mereka peroleh sewaktu dahulu menjadi anak perempuan.
Tabel IV.C.3.1. Perbandingan Perubahan Nilai-nilai yang Disosialisasikan
pada Ibu
Ibu Lely Ibu Olga
- Ibu Lely menyadari adanya
perubahan nilai-nilai dari yang ia
alami sebagai anak perempuan
dengan apa yang ia tanamkan
sebagai ibu kepada anak-anak
perempuannya. Ia merasa
perubahan ini merupakan hasil dari
pengalamannya sebagai anak
perempuan.
- Perubahan paling besar yang
dirasakan dan disosialisasikan
terkait dengan kebebasan untuk
beraktivitas dan
mengaktualisasikan diri dalam
berbagai kegiatan.
- Ibu Lely juga menyadari adanya
perbedaan cara mendidik antara
anak pertama, kedua dan ketiga
walaupun sama-sama perempuan.
- Ibu Olga menyadari perubahan
nilai-nilai yang disosialisasikan
pada keluarga intinya saat ini.
Perubahan-perubahan tersebut
berasal dari ketidakpuasannya
sebagai anak di keluarganya
terdahulu.
- Ketika membangun keluarga
sendiri ia berusaha memberikan
keterbukaan dan kebebasan yang
dahulu ia rindukan.
- Ibu Olga menyadari bahwa dulu ia
tidak dekat dengan orang tuanya.
Hal ini dikarenakan kehidupan
yang begitu sibuk dan keras
sehingga orang tuanya terfokus
pada usaha untuk menghidupi
keluarga.
- Ibu Olga berupaya agar di dalam
keluarganya sekarang ia dapat
menjalin kedekatan dengan anak-
anaknya melalui obrolan.
- Ibu Olga menyadari bahwa anak-
anaknya tidak akan bisa menjadi
pribadi yang sekuat Ibu Olga. Ia
sering merasa terlalu memanjakan
anak-anaknya dengan kehidupan
yang terlalu nyaman.
Perubahan dimulai melalui keputusan Ibu Lely dan Ibu Olga memilih
sendiri pasangan hidupnya. Ibu Lely dan Ibu Olga sudah tidak mengalami
perjodohan seperti yang dituliskan Meij (2009) dalam disertasinya. Keberanian
untuk memilih jodoh atas kehendak sendiri menjadikan pernikahan sebagai sarana
93
aktualisasi bagi Ibu Lely dan Ibu Olga untuk mengaktualisasikan diri. Selain itu,
pernikahan juga menjadi sarana menyalurkan keinginan terpendam yang tidak
terfasilitasi ketika dulu menjadi anak perempuan. Kini, dengan peran sebagai ibu
mereka memiliki hak dan kebebasan untuk mendidik anak-anak perempuan sesuai
keinginan mereka.
Perubahan sosialisasi melalui pola asuh disadari oleh Retha, anak dari Ibu
Lely dan Shinta, anak dari Ibu Olga seperti tampak dalam tabel IV.C.3.2. berikut
ini.
Tabel IV.C.3.2. Perbandingan Perubahan Nilai-nilai yang Disosialisasikan
pada Anak Perempuan
Retha Shinta
- Retha menyadari adanya perubahan
nilai yang disosialisasikan. Ia
mengetahui perubahan ini terjadi
karena ibunya merasa ada hal-hal
yang tidak cocok dari pendidikan
yang diberikan oleh popo (Ibu dari
ibunya) terhadap ibunya.
- Pengetahuan dan kesadaran ini
membantu Retha untuk memahami
mengapa ibunya mendidik dan
mendorong anak-anaknya seperti
sekarang ini untuk berkegiatan dan
beraktivitas di luar rumah.
Perbedaan ini berlandaskan prinsip
yang dianut oleh Ibu Lely.
- Shinta membenarkan bahwa ibunya
sering menceritakan bagaimana
pengalaman hidupnya dahulu.
Bahkan pengalaman hidup ibunya
mempengaruhi keputusan Shinta
untuk melanjutkan sekolah.
- Shinta mensyukuri kehidupannya di
masa sekarang ini. Ia tidak bisa
membayangkan bagaimana hidup di
zaman ibunya tanpa kemudahan
hidup dan kecanggihan teknologi
seperti sekarang ini.
- Kesadaran akan perubahan nilai-
nilai yang disosialisasikan
dirasakan Shinta lebih dipengaruhi
karena posisinya sebagai anak
pertama serta pengalamannya
pernah mencicipi kehidupan di luar
negeri.
Shinta memiliki penghayatan yang berbeda dengan Retha dalam hal
kesadaran akan perubahan nilai-nilai yang disosialisasikan. Dari hasil wawancara,
94
tampak bagaimana posisi Shinta sebagai anak pertama mendapatkan tekanan dan
tuntutan yang lebih tinggi dibandingkan adik-adiknya. Sebenarnya hal ini juga
terjadi pada anak perempuan di keluarga Ibu Lely. Retha, sebagai anak kedua
menyadari bagaimana kakak perempuannya lebih dilarang dan dibatasi dalam
bergaul serta dituntut untuk memberi contoh yang baik bagi adik-adiknya.
Terlepas dari perbedaan penghayatan Retha dan Shinta yang disebabkan
oleh urutan kelahiran, terlihat bagaimana perubahan nilai-nilai yang
disosialisasikan. Dari pengalaman Ibu Lely dan Ibu Olga sebagai anak perempuan
keluarga Tionghoa dengan pengalaman Retha dan Shinta sebagai anak dari Ibu
Lely dan Ibu Olga terlihat perubahan nilai terjadi karena pengalaman para ibu.
Hal ini sesuai dengan telaah Nani Nurrachman (2011) terhadap teori
Chodorow, yaitu proses menjadi ibu merupakan suatu sublimasi psikologis dari si
ibu. Hal-hal yang dahulu mereka rindukan sebagai anak perempuan seperti
kebebasan berpendapat dan kedekatan dengan orang tua, dikejewantahkan oleh
Ibu Lely dan Ibu Olga dalam interaksi mereka dengan anak-anaknya saat ini.
Retha dan Shinta pun menyadari adanya perubahan nilai yang
disosialisasikan oleh ibu mereka. Kesadaran ini diperoleh dari cerita pengalaman
hidup ibu yang diceritakan kepada Retha dan Shinta. Kemudian, Retha dan Shinta
membandingkan dengan pengalaman mereka sendiri sebagai anak perempuan.
Proses naratif (story telling) membantu anak perempuan untuk merefleksi,
mengevaluasi dan mengkonstruksi dirinya sendiri.
95
Pada dinamika ini, self-in relation (Chodorow, 1978) berperan dalam
membantu Ibu Lely dan Ibu Olga merefleksikan, mengevaluasi dan
mengkonstruksi kehidupan mereka sebagai anak perempuan, terutama dalam
relasi dengan ibu. Pada Retha dan Shinta, self-in relation (Chodorow, 1978)
berperan dalam memahami sejarah hidup ibu mereka dan apa yang mereka alami
saat ini sebagai anak perempuan. Hal ini tercermin dalam sosialisasi identitas
gender yang terjadi pada para responden penelitian.
IV.C.4. Sosialisasi Identitas Gender pada Anak Perempuan
Pada tabel IV.C.4.1. terdapat perbandingan sosialisasi identitas gender
yang diberikan oleh Ibu Lely dan Ibu Olga kepada anak perempuannya.
Sosialisasi identitas gender ini dipengaruhi nilai-nilai pengasuhan dan pengalaman
Ibu Lely dan Ibu Olga yang terinternalisasi di dalam diri. Ibu Lely dan Ibu Olga
mengkombinasikan nilai-nilai yang mereka anggap baik dari keluarga Tionghoa,
seperti nilai kepercayaan, kejujuran, kedisiplinan dan kerja keras dengan lebih
melibatkan unsur afeksi dan dialog dengan anak.
Tabel IV.C.4.1. Perbandingan Sosialisasi Identitas Gender dari Ibu
Ibu Lely Ibu Olga
- Ibu Lely merasa hal yang paling
sering ia tanamkan kepada anak-
anak perempuannya adalah nilai
kepercayaan. Sebab menurutnya
kepercayaan adalah suatu hal yang
tidak bisa dibeli, sekaya apapun
seseorang
- Menurut Ibu Lely apa yang ia
lakukan merupakan suatu proses
kehidupan yang mengalir dan
dijalani saja.
- Kakak dan adiknya yang laki-laki
diperkenankan tidak membantu
mengurusi rumah. Kakaknya yang
laki-laki merupakan anak yang
pintar di sekolah, sehingga ia
diberikan kesempatan untuk
memakai waktunya untuk belajar.
- Ibu Olga mendidik anak-anak
perempuannya untuk memiliki
sikap menghormati, terutama pada
yang lebih tua serta menjaga rasa
96
- Nilai-nilai yang disosialisasikan
lebih disadari oleh Retha, anak ibu
Lely daripada Ibu Lely sendiri.
kekeluargaan.
- Ibu Olga juga berusaha
mengajarkan dan menanamkan
nilai kerja keras pada anak-
anaknya dengan menceritakan
kisah hidupnya yang penuh
perjuangan pada anak-anaknya.
Pada Ibu Lely-Retha, menariknya kesadaran akan nilai-nilai yang
disosialisasikan lebih muncul pada diri Retha daripada ibunya. Pada proses
wawancara, Retha lebih dapat mengelaborasi nilai-nilai yang ia rasakan
disosialisasikan oleh ibunya daripada ibunya sendiri. Sementara Ibu Olga terlihat
lebih sadar, tahu dan meyakini apa yang disosialisasikan pada anak
perempuannya.
Sublimasi psikologis melalui peran Ibu seperti dalam teori Chodorow
(1978) tidak serta merta membuat para ibu steril dari pengalaman masa lalunya.
Pada Ibu Lely terlihat bagaimana kekakuan pola asuh ibunya masih
mempengaruhi Ibu Lely dalam berinteraksi dengan anak perempuannya,
walaupun Ibu Lely sudah berusaha untuk lebih terbuka dengan anak. Ibu Olga
yang terbiasa dengan pola asuh otoriter juga tidak dengan mudah dapat berdiskusi
setara dengan anak. Di masa anak-anak lebih kecil, Ibu Olga masih sering
mendisiplinkan anak dengan pukulan atau hukuman fisik. Ketika Shinta beranjak
dewasa, Ibu Olga baru lebih dapat berdiskusi setara dan dua arah dengan anaknya.
Pemahaman sosialisasi identitas gender pada diri anak perempuan, Retha
dan Shinta dapat dilihat pada tabel IV.C.4.2. berikut ini.
97
Tabel IV.C.4.2. Perbandingan Sosialisasi Identitas Gender pada Anak
Perempuan
Retha Shinta
- Ia merasa ibunya menekankan nilai
kepercayaan ini kepada dirinya.
Namun Retha memiliki pemaknaan
yang berbeda tentang kepercayaan
yang ditanamkan oleh ibunya.
- Retha memaknai kepercayaan yang
diberikan oleh ibunya sebagai
kepercayaan untuk beraktivitas di
luar rumah.
- Kepercayaan ini merupakan hasil
dari pengalaman ibunya yang
dahulu tidak diperbolehkan
bepergian ke mana-mana oleh
ibunya.
- Retha juga merasa ibunya
mengajarkan nilai kedisiplinan
padanya. Walaupun ia merasa
ibunya tidak sekeras itu
menanamkan kedisiplinan pada
adiknya yang merupakan anak
ketiga.
- Dari segi afeksi, Retha merasa
ibunya bukanlah sosok ibu yang
sering memeluk atau melakukan
kontak fisik dengan anaknya.
Menurut Retha, hal ini disebabkan
karena ibunya dulu mendapat
didikan dari ibunya seperti ini
- Ia menyadari kalau ibunya kurang
memberikan pendidikan seksualitas
ini. Ia menduga karena ibunya
sendiri pun merasa aneh dan tidak
biasa membicarakan hal ini saat
bersama ibunya dahulu.
- Nilai-nilai yang ditanamkan ibunya
ini dilakukan melalui berbagai
peristiwa hidup yang relevan.
Namun tidak ada waktu khusus
seperti duduk bersama di meja
makan untuk membicarakan hal-
- Shinta merasa nilai kerja keras
yang ditanamkan oleh ibunya
merupakan bagian dari nilai
(value) yang dimiliki oleh orang
Cina pada umumnya.
- Shinta juga diajarkan untuk
menghormati orang yang lebih tua.
- Menurut Shinta, ibunya sangat
menekankan pada ketiga anaknya
untuk dapat hidup mandiri tanpa
bergantung pada orang lain.
- Pada waktu ia kecil, ibunya
tergolong tegas dalam
mendisiplinkan anak. Terutama
berkaitan dengan nilai akademis di
sekolah dan kepatuhan menjalani
peraturan di rumah
- Shinta merasa dapat mengobrol
dengan akrab dan berdiskusi
secara setara dengan ibunya.
- Shinta menyadari hubungan yang
setara dengan ibunya baru
dirasakannya akhir-akhir ini ketika
semakin beranjak dewasa.
Sementara pada waktu ia kecil,
ibunya tergolong tegas dalam
mendisiplinkan anak
- Shinta menyetujui pola hubungan
seperti yang ia alami bersama
ibunya. Anak bisa berdiskusi
dengan orang tua namun juga tetap
hormat pada orang tua.
- Shinta merasa adanya perbedaan
98
hal seperti ini.
- Retha merasa dirinya berbeda
dengan ibunya dalam hal
pembawaan diri, kepribadian dan
cara bergaul. Ibu cenderung kaku
sementara ia merasa dirinya
sebagai orang yang supel dan
cerewet dalam bergaul.
antara dirinya dan ibunya terutama
dalam hal pemikiran. Menurut
Shinta, ibunya sering
mengkhawatirkan hal-hal yang
menurutnya tidak perlu
dikhawatirkan. Salah satunya
tentang masa depan anak-anak
perempuannya.
IV.C.5. Pengalaman Ibu dan Anak Perempuan dengan Identitas Ke-
Tionghoa-an
Identitas ke-Tionghoa-an dimaknai berbeda oleh Ibu Lely dan Ibu Olga.
Pemaknaan yang berbeda ini terkait dengan pengalaman hidup Ibu Lely dan Ibu
Olga sebagai perempuan keturunan Tionghoa di Indonesia.
Tabel IV.C.5.1. Perbandingan Pengalaman Ibu dengan Identitas Ke-
Tionghoa-an
Ibu Lely Ibu Olga
- Sejak kecil ia merasa sebagai warga
minoritas di mana identitas ke-
Tionghoa-an selalu melekat dengan
dirinya. Walaupun ia berupaya
untuk menjadi sama, tetap saja pada
kenyataannya tetap terjadi
pembedaan. Hal ini ia rasakan sejak
kecil dalam lingkungan pergaulan
dan masyarakat yang di mana ia
berinteraksi.
- Dulu, ketika Ibu Lely lewat di jalan
ia sering sekali dikatai dengan
sebutan “Amoy”. Ia merasa sangat
tidak nyaman dengan sebutan ini.
- Ia pun merasa adanya tiga nama
yang ia miliki membuatnya sudah
dijauhi orang dari awal.
- Ia berpikir dengan adanya
pergantian nama ia dapat lebih
diterima di masyarakat. Namun
ternyata setelah pergantian nama
dan naturalisasi kewarganegaraan
- Ibu Olga pernah mengalami
bersekolah di sekolah negeri di
tingkat sekolah dasar. Saat itu, ia
satu-satunya keturunan Tionghoa
di sekolah. Bahkan di antara
kakak dan adiknya, ibu Olga
merupakan satu-satunya anak
yang pernah bersekolah di sekolah
negeri.
- Ibu Olga dapat dengan mantap
dan yakin mengakui dirinya
sebagai orang Indonesia. Sebab ia
lahir dan besar di Indonesia.
Sampai mati pun akan tetap
menjadi orang Indonesia.
99
pun nama marga Tionghoa-nya
tetap diperlukan dalam setiap
pengurusan surat kewarganegaraan.
- Sampai hari ini pun, Ibu Lely masih
merasakan perbedaan perlakuan
karena identitas ke-Tionghoaan-
nya.
Pada Retha dan Shinta, pengalaman dan penghayatan Ibu tentang ke-
Tionghoa-an mempengaruhi penanaman nilai ke-Tionghoaan pada diri mereka.
Namun pengalaman individual mereka juga mempengaruhi penghayatan Retha
dan Shinta terhadap identitas ke-Tionghoaan.
Tabel IV.C.5.2. Perbandingan Pengalaman Anak Perempuan dengan
Identitas Ke-Tionghoa-an
Retha Shinta
- Retha merasa pada generasinya
sekarang ini ia merasa ia sudah
lebih bisa berbaur dengan yang
lainnya.
- Retha masih mengalami beberapa
peristiwa di mana identitas ke-
Tionghoa-annya menjadi bahan
ledekan oleh temannya.
- Pada masa sekolah, teman yang
meledeknya ini justru adalah orang
Tionghoa juga. Sementara dalam
kehidupan perkuliahan, ledekan
menggunakan identitas ke-
Tionghoa-an muncul dalam
stereotipe yang juga digunakan
untuk suku-suku lain. Namun ia
memaklumi ini sebagai bagian dari
dinamika perkembangan dewasa
muda.
- Retha merasa dari keluarga
terutama oleh ibunya ditanamkan
identitas ke-Tionghoa-an ini.
- Retha menilai hal ini sebagai suatu
hal yang baik sebab menurutnya
- Shinta merasa sebagai minoritas
dengan identitas ke-Tionghoaannya.
Waktu di sekolah dasar ia sempat
bersekolah di sekolah strada yang
mayoritas “pribumi”. Ia dan adiknya
sering menjadi bahan ledekan
- Ia merasa tidak nyaman ketika
diledek dengan sebutan “Mei Mei”
saat berjalan di trotoar sepulang
mengikuti bimbingan belajar di
SMAN 8.
- Ketika ditanya mengenai
identitasnya, Shinta merasa ia
berada di antara (in between) antara
merasa sebagai orang Indonesia dan
Australia.
- Shinta merasa ibunya tidak
menanamkan identitas ke-
Tionghoaan secara khusus karena
sudah banyak tradisi yang tidak
dilakukan
100
seorang manusia itu harus memiliki
akar. Ia merasa kesadaran dan
penanaman akan akarnya ini
membantunya pada masa SMP-
SMA ketika proses pencarian jati
diri.
- Retha merasa ibunya tidak
memberikan batasan untuk
berteman dengan siapa saja.
Namun ibunya menginginkan
anaknya mendapatkan pasangan
yang juga keturunan Tionghoa.
Seandainya bukan keturunan
Tionghoa, tapi bisa berbaur dengan
keluarga mereka.
- Shinta merasa ibunya tidak
memberikan batasan untuk
berteman dengan siapa saja. Namun
untuk memilih pasangan hidup
jangan memilih yang beragama
Islam.
IV.D. Dinamika Penghayatan Peran Ibu dalam Sosialisasi Gender pada
Anak Perempuan di Keluarga Tionghoa
Ibu Lely dan Ibu Olga memperlihatkan bagaimana pengalaman hidup
mereka sebagai anak perempuan keluarga Tionghoa membentuk persepsi dan
perilaku mereka dalam berbagai keputusan hidup, terutama ketika mendidik anak
perempuannya. Ibu Lely dan Ibu Olga sama-sama lahir dan besar di Jakarta pada
kurun waktu tahun 1958-1966. Saat itu Indonesia baru memasuki dasawarsa
kedua sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat
Indonesia sedang merintis kehidupan di negara ini sehingga mayoritas masyarakat
berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini juga dialami
oleh keluarga Ibu Lely dan Ibu Olga. Kehadiran mereka sebagai keluarga
keturunan Tionghoa generasi kedua dan ketiga membuat orang tua mereka bekerja
keras demi menghidupi kebutuhan keluarga. Pada zaman itu pengendalian jumlah
101
keluarga melalui kontrasepsi belum tersosialisasi seperti sekarang. Ibu Olga lahir
sebagai anak dari enam bersaudara, Ibu Lely lahir dari sepuluh bersaudara.
Pendidikan yang rendah membatasi lapangan pekerjaan yang dapat
dijalani oleh orang tua mereka. Maka pekerjaan kasar dan berat pun dilakukan
untuk menyokong kebutuhan keluarga. Ibu Lely dan Ibu Olga lahir dan tumbuh
berkembang dalam kondisi prihatin yang seperti ini. Membantu jalannya
kehidupan rumah tangga dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik
menjadi aktivitas keseharian mereka sejak usia belia sebagai anak perempuan
keluarga Tionghoa.
Saudara laki-laki mereka boleh tidak ikut membantu di rumah. Bahkan
cenderung tidak diberikan tuntutan untuk membantu pekerjaan rumah tangga dan
dibebaskan untuk bermain. Ruang kebebasan dan kesempatan untuk
mengaktualisasikan diri begitu terbatas bagi Ibu Lely dan Ibu Olga. Sebab di mata
orang tua mereka yang utama adalah bagaimana menjaga kehidupan keluarga
sebagai satu entitas tetap berlangsung. Praktis tak ada ruang privat atau hak
sebagai individu.
Di dalam kehidupan keluarga Tionghoa yang kolektif, tak ada kesempatan
bagi mereka untuk mengaktualisasikan diri. Otoritas orang tua dan sikap
kepatuhan yang besar membuat mereka mematuhi saja permintaan dan peraturan
orang tua tanpa berani untuk membantah. Terasa ada kesenjangan kekuasaan di
dalam keluarga di mana orang tua menjadi atasan dan anak hanyalah bawahan
102
yang harus selalu menurut. Namun melalui pengalaman hidup seperti ini
sebenarnya keloyalitasan mereka kepada keluarga sedang dibentuk dan diasah.
Dari tampak luar perilaku mereka, Ibu Lely dan Ibu Olga tampak
menjalani kehidupan sebagai anak perempuan dengan penuh kepatuhan dan rasa
tanggung jawab kepada keluarga. Walaupun demikian, di dalam menjalani
perannya sebagai anak perempuan mereka menyimpan ketidaknyamanan dan
ketidaksetujuan atas pola asuh yang mereka alami. Diri perempuan mereka dalam
budaya kolektif menunjukkan bagaimana diri (self) perempuan didefinisikan
melalui hubungan mereka dengan orang lain. Meski mereka tidak nyaman dan
tidak setuju dengan kehidupan yang mereka jalani tapi mereka tidak begitu saja
mengeluarkan protes atau penolakan. Mereka tetap berusaha melakukan segala hal
yang diinginkan orang tua mereka.
Mereka menyadari tak ada jalan lain untuk mengaktualisasikan diri dan
menjalani hidup berdasarkan kepenuhan hak mereka selain dengan menikah.
Menikah dirasakan oleh Ibu Lely dan Ibu Olga sebagai sarana untuk membangun
hidup yang baru di atas tangan, kaki dan kehendak mereka sendiri. Ibu Lely dan
Ibu Olga tetap berupaya menjalani peran mereka sebagai istri dan partner dari
suami. Namun kehidupan keluarga inti mereka yang sekarang terlebih dengan
kehadiran anak-anak memberikan mereka ruang gerak baru untuk memaknai
kehidupan.
Pengalaman hidup sebagai anak perempuan di keluarga Tionghoa menjadi
sarana reflektif untuk mengambil hal-hal baik dan mentransformasi hal-hal negatif
103
yang mereka alami. Kini ketika menjadi ibu, mereka memiliki kuasa dan hak
penuh untuk mendidik dan memberikan pengalaman hidup pada anak-anak
perempuan mereka sesuai dengan keinginan terpendam mereka.
Ibu Lely yang mendambakan kebebasan untuk beraktualisasi di luar
rumah, mendorong dan memberikan kebebasan pada anak-anaknya untuk
mengaktualisasikan diri melalui kegiatan organisasi dan gereja. Ibu Lely yang
begitu ingin sekolah namun tak memiliki kesempatan dan biaya berusaha sekuat
tenaga untuk dapat menyekolahkan ketiga anaknya hingga menjadi sarjana.
Ibu Olga yang mendambakan keterbukaan di dalam keluarga berusaha
membangun hubungan yang akrab dengan anak-anaknya. Interaksi dengan anak-
anak diisi dengan obrolan, diskusi dan aktivitas yang membuat Ibu Olga merasa
dekat dengan anak-anak. Meskipun tetap ada kedisiplinan dan peraturan yang
ditegakkan di dalam keluarga namun Ibu Lely maupun Ibu Olga memberi
sentuhan personal mereka dalam mengemas interaksi dengan anak-anak.
Melalui penuturan Ibu Lely dan Ibu Olga atas pengalaman hidup mereka
terlihat bagaimana proses transformasi atas kehidupan di keluarga Tionghoa.
Agen transformasi ini adalah Ibu Lely dan Ibu Olga sendiri yang telah merasakan
bagaimana dididik sebagai anak perempuan. Lalu saat mereka memiliki anak
perempuan, mereka yang paling tahu hal apa yang ingin mereka ubah dan hal
yang yang tetap mereka pertahankan dalam mendidik anak-anaknya.
Secara garis besar, terjadi perubahan pemaknaan diri sebagai perempuan
di dalam keluarga Tionghoa. Anak perempuan tidak lagi menjadi warga kelas dua.
104
Mereka kini memiliki hak yang sama seperti anak laki-laki. Mereka memiliki
kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan diri dan mewujudkan cita-cita.
Bibit-bibit kesetaraan di dalam keluarga mulai terlihat meskipun anak perempuan
tetap diberikan tuntutan untuk dapat mengurus rumah dan keluarga. Namun
implementasinya tidak sekaku pada generasi Ibu Lely dan Ibu Olga.
Hasil analisa ini sesuai perkataan Nani Nurrachman (2011) bahwa proses
hamil dan melahirkan adalah proses biologis, namun menjadi ibu adalah sublimasi
psikologis. Ibu Lely dan Ibu Olga membuktikan bagaimana tekanan, konflik dan
pengalaman yang tidak mengenakkan sebagai anak perempuan mentransformasi
pola asuh, penanaman nilai dan sosialisasi gender pada anak-anak perempuan
mereka.
Sosialisasi identitas gender yang dialami oleh Retha dan Shinta, anak dari
Ibu Lely dan Ibu Olga, dapat dikatakan sebagai sosialisasi gender yang umum.
Mereka dipandang sebagai entitas individu, bukan lagi sebagai anak perempuan
karena jenis kelamin. Bagi ibunya, Retha dan Shinta adalah individu yang punyak
hak penuh untuk mengaktualisasikan diri serta mewujudkan cita-cita yang mereka
inginkan. Tak ada lagi batasan mengaktualisasikan diri karena tuntutan untuk
segera menikah. Bahkan Ibu Olga berani membebaskan anaknya untuk menikah
atau melajang. Baginya yang penting apapun pilihan hidup anaknya memberikan
kebahagian bagi diri mereka sendiri.
Ketika kesempatan untuk mengaktualisasikan diri menjadi begitu terbuka
lebar dari pihak keluarga inti, Retha dan Shinta ternyata masih mengalami
105
hambatan dari lingkungan masyarakat. Hambatan ini muncul dari identitas etnis
mereka sebagai keturunan Tionghoa di Indonesia. Sampai hari ini stereotipe dan
prasangka (prejudice) terhadap etnis Tionghoa secara nyata masih dirasakan
Retha dan Shinta dalam interaksi mereka di masyarakat.
Isu kesetaraan bagi mereka bukan lagi berkutat pada identitas gender,
tetapi pada identitas keetnisan. Hal ini menjadi suatu penemuan baru dalam
penelitian ini. Sebab pada awalnya peneliti melihat fenomena identitas gender
menghalangi anak perempuan di keluarga Tionghoa untuk mengaktualisasikan
diri. Ternyata pada Retha dan Shinta sebagai subjek penelitian, mereka lebih
merasakan ketimpangan pada penerimaan diri mereka di dalam ke-Indonesia-an.
Retha dan Shinta merupakan potret dari segregasi dan diskriminasi etnis
Tionghoa dalam masyarakat yang masih terjadi sampai hari ini meskipun rezim
Orde Baru sudah berakhir. Ketidaksetaraan di dalam masyarakat ini memberikan
ketidaknyamanan bagi mereka. Namun dari hasil observasi sebenarnya tampak
adanya represi dan rasionalisasi terhadap ketidaknyamanan ini.
Akhirnya, pengalaman berinteraksi di dalam masyarakat menjadi hal yang
tidak nyaman bagi mereka. Hal ini tdialami oleh Ibu Lely, Retha dan Shinta.
Bentuk wajah dan ciri-ciri fisik mereka yang menunjukkan identitas ke-Tionghoa-
an memunculkan pelecehan verbal melalui ledekan “Amoy” atau “Mei-Mei” dari
orang “pribumi” atau mereka sebut dengan “abang-abang” saat berpapasan di
jalan umum.
106
Dampak dari pelecehan verbal dan prasangka ini secara nyata terlihat pada
Ibu Lely yang merasa tidak nyaman jika berada dalam situasi yang mayoritas
adalah “pribumi”. Ia cenderung menghindari tempat-tempat umum seperti
angkutan umum dan pusat perbelanjaan yang mayoritas didatangi oleh “pribumi”.
Terlihat bagaimana ketidaknyamanan Ibu Lely yang merasa di-Cina-kan oleh
masyarakat mempengaruhi perilaku dan keputusan dalam aktivitas hidupnya.
Berbeda dari yang lain, Ibu Olga merasa sebagai orang Indonesia dan
nyaman tinggal di negara ini. Ia merasa seluruh kebutuhan hidup dapat terpenuhi
dengan tinggal di negara ini. Saat ini ia juga menikmati kehidupan yang
berkecukupan. Status sosial ekonomi kemungkinan memberikan kontribusi
kenyamanan bagi Ibu Olga. Namun jika dilihat dari generasi migrasi, keluarga Ibu
Olga secara turun temurun telah lebih lama menetap di Indonesia. Melalui
penelusuran historis ditemukan nenek dari Ibu Olga sehari-hari menggunakan
pakaian kebaya dan ibunya menggunakan rok-kemeja. Sementara nenek dari Ibu
Lely masih tinggal di Cina. Nenek dan ibu dari Ibu Lely dalam keseharian masih
menggunakan pakaian Cina.
Melalui penelitian ini terlihat bagaimana dinamika peran penghayatan ibu
telah mampu mentransformasi sosialisasi gender pada anak perempuan di
keluarga Tionghoa. Transformasi ini tergolong cepat sebab terjadi pada satu
generasi sesudah para ibu. Terlihat bagaimana ibu menjadi agen sosialisasi yang
aktif bagi anak-anak perempuannya. Keberhasilan ibu sebagai transformator tidak
terlepas dari kehadiran anak yang melegitimasi kemampuan para ibu merubah
107
pemaknaan hidup secara internal. Perubahan di dalam internal diri mereka
merubah konteks eksternal kehidupan mereka.
Dari segi pendidikan formal, Ibu Lely sempat mengenyam pendidikan dasar
di sekolah Cina berbahasa Mandarin. Sementara Ibu Olga yang lahir setelah
peristiwa G-30S, mengenyam pendidikan di sekolah negeri dan sekolah Katolik.
Penelitian ini tidak secara khusus membahas dampak dari sosialisasi identitas
yang diperoleh melalui pendidikan formal. Namun dari penuturan Ibu Lely dan
Ibu Olga terlihat bagaimana modalitas pribadi mempengaruhi cara coping ketika
mengalami diskriminasi.
Pada Ibu Lely yang memiliki ibu yang kaku dan tidak bisa bergaul, ia
kesulitan untuk menyikapi diskriminasi yang ia alami. Akhirnya ia menjustifikasi
diri pada label ke-Cina-an yang diberikan oleh lingkungan terhadapnya, meskipun
ia sendiri merasa tidak nyaman. Ia merasa tidak berdaya terhadap lingkungan
sosialnya, namun ia mentransmisikan rasa tidak suka dan tidak terima terhadap
perlakuan ini kepada anak perempuannya. Maka pada Retha ia mengakui lebih
merasa Cina ketimbang Indonesia ataupun Cina-Indonesia meskipun dalam
praktek kehidupan sehari-hari ia lebih fleksibel dan mampu beradaptasi
dibandingkan ibunya.
Pada Ibu Olga, ia juga mengalami diskriminasi saat bersekolah di sekolah
negeri. Namun ia tidak larut dalam perasaan sebagai korban. Ia menyikapi
diskriminasi ini dengan mendatangi teman-teman sekolah yang mem-bully Ibu
Olga. Setelah beberapa kali melakukan proses seperti ini, Ibu Olga akhirnya
108
diterima oleh teman-teman non-Tionghoa, bahkan mereka masih berteman akrab
sampai sekarang. Maka, modalitas ibu sebagai individu amatlah penting untuk
mendefinisikan diri sesuai pengalaman, penghayatan dan interpretasinya. Serta
untuk menghadapi lingkungan sosial yang membedakan mereka.
Para ibu berhasil mensosialisasikan identitas gender yang lebih setara pada
anak perempuannya. Namun dari segi budaya Tionghoa para ibu telah mereduksi
internalisasi identitas ke-Tionghoa-an. Tradisi dalam budaya Tionghoa yang
berkaitan dengan penggunaan nama Tionghoa, ritual dalam merayakan hari besar
budaya Tionghoa dan nilai-nilai keluhuran Konfusius yang menjadi dasar
kehidupan keluarga Tionghoa. Sementara di sisi lain, nilai komunal keluarga tetap
diharapkan dan dijunjung tinggi.
109
BAB V
KESIMPULAN, SARAN DAN DISKUSI
V.A. KESIMPULAN
Peran Ibu di keluarga Tionghoa adalah sebagai agen perubahan.
Perubahan ini berasal dari pengalaman mereka sebagai anak perempuan yang
dibedakan dari anak laki-laki. Kondisi mereka sebagai anak di keluarga yang
patriarkis menyebabkan mereka tidak memiliki kuasa untuk mengubah keadaan.
Mereka berusaha menjalani peran sebagai anak dengan patuh. Namun secara
psikologis di dunia internal (psyche), tersimpan penolakan terhadap peristiwa
hidup yang dialami.
Perubahan baru bisa dilakukan ketika anak perempuan menikah dan
membentuk keluarga baru berdasarkan keputusan mereka sendiri. Pernikahan
dipandang sebagai sarana untuk melepaskan diri dari tekanan di keluarga
terdahulu. Ketika anak perempuan membentuk keluarga sendiri, posisi mereka
berubah dari anak menjadi istri dan ibu dari keluarga baru. Mereka tidak lagi
menempati posisi yang inferior.
Maka kekuasaan penuh terhadap keputusan hidup ada di tangan mereka.
Peran sebagai ibu memberikan mereka keleluasaan dan kebebasan untuk
mendidik anak berdasarkan apa yang mereka inginkan. Termasuk apa yang
mereka inginkan namun tidak dapat mereka alami sebagai anak perempuan dahulu
kala.
110
Peran ibu sebagai agen perubahan, memberikan implikasi adanya
perubahan sosialisasi identitas gender pada anak perempuan di keluarga
Tionghoa. Ibu mendidik anak perempuan tanpa pembedaan gender dengan
memberikan kebebasan dan keterbukaan. Dengan demikian anak perempuan
dalam penelitian ini tidak lagi merasa dirinya berbeda dengan laki-laki dalam
mengaktualisasikan diri.
V.B. Diskusi
Pengalaman Ibu yang tidak mengenakkan pada waktu ia sebagai anak dan
tidak adanya kesempatan mewujudkan aspirasinya, mempengaruhi cara Ibu
membesarkan dan mendidik anaknya. Melalui perspektif psikodinamika, terlihat
Ibu melakukan proyeksi pada anaknya. Ini menjadi landasan pola asuh yang Ibu
berikan kepada anak perempuan mereka. Kebebasan dan keterbukaan yang tidak
mereka dapatkan sebagai anak, kini mereka berikan kepada anak perempuan
mereka. Perubahan ini menyebabkan identitas gender dipahami secara setara
antara laki-laki dan perempuan, mereka menyadari bahwa mereka memiliki hak
yang sama dengan laki-laki untuk berkembang dan mengaktualisasikan diri.
Namun di sisi lain mereka menyadari bahwa identitas ke-Tionghoa-an
mereka memberikan batasan untuk mengaktualisasikan diri di dalam masyarakat.
Melalui penelitian ini terlihat masalah baru yang lebih krusial, yaitu bagaimana
identitas etnis menghalangi aktualisasi diri para perempuan Tionghoa di
masyarakat
111
Pada tahun 1979 dan 1984, Myra Sidharta pernah membuat tulisan
“Wanita Peranakan Cinta” dan “The Making of Indonesian Chinese Woman”
yang menceritakan bagaimana kehidupan perempuan Tionghoa Indonesia dari
tahun 1920-an, 1940-an hingga 1970-an. Pada perkembangan zaman sekarang ini,
tulisan tersebut tidak lagi relevan untuk memahami perempuan Tionghoa di masa
kini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi awal dari penelitian
selanjutnya untuk mengkonstruksi apa artinya menjadi perempuan Tionghoa-
Indonesia di masa kini.
Menurut peneliti, identitas keetnisan dibebankan kepada para perempuan
Tionghoa Indonesia semata-mata karena tampilan fisik mereka yang berkulit
kuning langsat dan bermata sipit. Padahal di dalam diri mereka sendiri, belum
tentu mereka masih menghayati nilai-nilai ke-Tionghoa-an mereka seperti yang
ditemukan dari subyek penelitian ini. Maka pertanyaan yang muncul kemudian
adalah siapa yang berhak menentukan identitas keetnisan seseorang?
Merujuk pada teori pembentukan diri (self) yang terjadi melalui suatu hasil
interaksi. Bagaimana tarik menarik antara diri (self) yang dihayati oleh individu
dengan diri (self) yang dipandang dan diekspektasi oleh lingkungan sekitarnya?
Di titik mana perempuan Tionghoa Indonesia dapat memantapkan definisi
mengenai dirinya?
Pada titik ini sesungguhnya tersimpan isu laten yang lebih krusial. Jika
menurut teori Erikson (Santrock, 2008) seorang individu mempertanyakan
mengenai identitas dirinya di masa remaja pada tahap identity vs identity
112
confusion. Maka pada perempuan Tionghoa Indonesia pertanyaan mengenai
identitasnya masih terus bergulir di sepanjang rentang kehidupannya.
Terlebih lagi jika menyadari bahwa perempuan mendefinisikan dirinya
dalam hubungannya dengan orang lain atau self-in relation. Bagaimana orang lain
memberikan penilaian dan justifikasi akan mempengaruhi bagaimana perempuan
mendefinisikan dirinya. Tak heran jika ibu Lely, salah satu subyek penelitian
lebih merasa dirinya sebagai Cina ketimbang merasa sebagai orang Indonesia
dengan alasan “sebab dari kecil saya sudah di-Cina-Cinakan oleh orang-orang di
sekitar saya”.
Terdeteksi suatu gejala kebingungan di titik mana seharusnya perempuan
Tionghoa berpijak. Sebagai bagian dari masyarakat timur yang menjunjung
kolektivisme, diri (self) didefinisikan melalui interdependen dengan sistem sosial
yang melingkupinya (Aronson, 2008). Dimulai dari interdependen dalam lingkup
terkecil, yaitu keluarga sampai interdependen dalam cakupan yang lebih luas
seperti di dalam masyarakat Indonesia.
Maka di tengah keberhasilan para ibu sebagai transformator sosialisasi gender
sesungguhnya tersimpan isu laten mengenai identitas diri perempuan Tionghoa.
Sesungguhnya saat ini mereka sedang dan masih bergelut dalam upaya
mendefinisikan identitas diri. Diri (self) yang menjadi (becoming) masih menjadi
tema utama hidup mereka. Pergumulan masih akan terus berlangsung. Pertanyaan
selanjutnya adalah apakah pergumulan ini sungguh disadari oleh para perempuan
Tionghoa ataukah mereka menatap lurus ke depan mengabaikan dinamika internal
113
mereka yang selama ini memang cenderung diabaikan akibat represi dan
rasionalisasi terhadap pengalaman hidup yang tidak mengenakkan sebagai orang
keturunan Tionghoa di dalam masyarakat Indonesia.
Terkait dengan pemaparan Fischer (1991) pada Bab 1 penelitian ini
mengenai variabel-variabel yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian
mengenai ibu dan anak perempuan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
serupa pada etnis-etnis lain di Indonesia dengan mempertimbangkan faktor
demografi. Penelitian lintas budaya mengenai ibu dan anak perempuan dapat
menjadi sarana untuk mengetahui kondisi riil dan kontekstual mengenai
perubahan nilai-nilai yang ada di keluarga sebagai sistem terkecil dalam
masyarakat namun memiliki peran serta dampak yang signifikan dalam
pertumbuhkembangan manusia.
Penelitian ini memberikan kesadaran pada peneliti mengenai relevansi
pendapat R.A. Kartini pada kehidupan perempuan hingga zaman ini,
“...Perempuan sebagai pendukung peradaban! Saya yakin sungguh bahwa
dari perempuan akan timbul pengaruh besar, yang baik atau buruk akan
berakibat besar bagi kehidupan. Dari perempuanlah manusia itu pertama-tama
menerima pendidikan. Di pangkuan perempuanlah seseorang mulai belajar
merasa, berpikir dan berkata-kataa...dan bagaimanakah ibu-ibu dapat mendidik
anak-anaknya, kalau mereka sendiri tidak berpendidikan?” (Surat kepada
Nyonya M.C.E. Ovink-Soer, 2 November 1900 dalam Sulastin, 1977).
V.C. SARAN
114
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna. Adapun
kelemahan penelitian ini antara lain:
1. Keterbatasan literatur dan sumber terkini di bidang psikologi perempuan
Walaupun gerakan psikologi perempuan telah dimulai sejak tahun 1970-an
namun masih sedikit penelitian dalam bidang ini terlebih dalam konteks
Indonesia. Itu sebabnya peneliti sering menggunakan literatur lama atau
sumber literatur yang dominan dari penelitian tertentu di dalam penulisan
penelitian ini. Tulisan Ibu Myra Sidharta ‘The Making of Indonesian
Chinese Woman” didapatkan peneliti melalui korespondensi langsung
dengan beliau karena tidak dapat menemukan tulisan ini di perpustakaan
atau toko buku saat ini.
Di bawah ini akan dipaparkan saran metodologis untuk penelitian
selanjutnya maupun saran praktis.
V.C.1. Saran Metodologis
V.C.1.2. Pemilihan Subjek Penelitian
Walaupun topik penelitian ini merupakan topik umum namun ternyata cukup sulit
untuk menemukan subyek penelitian pasangan ibu dan anak perempuan yang
bersedia untuk menjadi responden. Subyek penelitian dituntut memiliki
kemampuan verbalisasi yang baik sehingga dapat menjelaskan pengalaman hidup
yang dialaminya. Selain itu, tanpa disadari kedua responden dalam penelitian ini
memiliki tiga anak perempuan, tanpa memiliki anak laki-laki. Pada penelitian
115
selanjutnya jenis kelamin anak dari ibu yang menjadi responden sebaiknya
diperhatikan juga agar mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai
pengasuhan ibu terhadap anak perempuan maupun anak laki-laki. Bahkan juga
dapat dilakukan penelitian perbandingan pola asuh ibu terhadap anak perempuan
dan anak laki-laki. Sebab menurut teori self-in relation Chodorow (1978)
dikatakan anak perempuan dan anak laki-laki membentuk self melalui relasi
dengan ibu. Anak perempuan membentuk self dengan connectedness pada ibu,
sementara anak laki-laki membentuk self dengan separation pada ibu.
V.C.2. Saran Praktis
1. Diperlukan keterbukaan dan ketergerakan dari dalam diri disertai dukungan
sosial yang kondusif sehingga para perempuan Tionghoa dapat belajar
mengakrabi dirinya sendiri.
2. Ibu dan anak perempuan dapat saling bersinergi dalam merekonstruksi
pemaknaan diri. Kebebasan yang telah dimiliki perempuan Tionghoa Indonesia
masa kini untuk mentransformasi hidupnya maupun anak-anaknya
3. Kesadaran dari ibu dan anak perempuan jika dimanfaatkan secara maksimal
dapat berguna untuk mentransformasi kehidupan masyarakat dan lingkungan
sekitarnya.
4. Modalitas diri seorang perempuan sangat mempengaruhi kemampuannya dalam
mengasuh anak. Sayangnya di masa kini, masih banyak perempuan yang take it
for granted dalam hal menikah, mengasuh anak dan menjadi ibu. Padahal melalui
116
relasi dengan diri ibu, diri manusia terbentuk dan dibentuk. Melalui penelusuran
literatur ditemukan konstruk baru, yaitu Psychological Readiness to Motherhood
(“Psychological Readiness”, 2010). Penelitian tentang ini pun masih minim.
Secara umum, hasil penelitian ini berguna bagi para pembuat kebijakan,
konselor dan aktivis bahwa usaha merubah tatanan kehidupan sosial yang makro,
seharusnya dimulai dari lingkup keluarga. Di dalam keluarga, ibu menjadi
protagonis kebudayaan yang memodifikasi, merevisi dan mentransformasi
kehidupan. Perubahan dimulai dari keluarga dan diprakarsai oleh ibu. Maka
mendidik anak-anak, remaja, dan dewasa muda perempuan yang nantinya akan
menjadi ibu adalah suatu keabsolutan demi mencapai perubahan yang maksimal.
Hal ini sesuai dengan peribahasa Afrika, “If you educate a man you
educate an individual, but if you educate a woman you educate a nation”.
1
DAFTAR PUSTAKA
4 Cinta Titi Sjuman. 23-29 April 2011. Femina, hlm58.
Arbaningsih, D. (2005). Kartini dari Sisi Lain: Melacak Pemikiran Kartini
tentang Emansipasi Bangsa. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Aronson, A. (2008). Social Psychology (7th ed.). Boston: Mc-Graw Hill.
Brouwer, M.A. (et, al.). (1982). Kepribadian dan Perubahannya. Jakarta: PT.
Gramedia.
Beasley, C. (2005). Gender & sexuality: critical theories, critical thinkers. Sage
Publications: London
Berk, L. (1997). Child development. Allyn & Bacon: Boston.
Carteret, M. (2011). Culture and family dynamic. Diakses pada tanggal 8 Juli
2012 dari http://www.dimensionsofculture.com/2010/11/culture-and-family-
dynamics/
Chodorow, N. (1978). The reproduction of mothering. California: The University
of California.
Correl, S., et al. (2007). The social psychology of gender: advanced in group
process. Vol, 24. Elsevier: Los Angeles
Creswell, J. (1994). Research design qualitative & quantitave approaches. Sage
Publications: California.
Cobb, N.J. (2001). The Child: infants, children, and adolescents. California:
Mayfield Publishing Company.
Dawis, A. (2008). Orang Tionghoa Indonesia Mencari Identitas. Jakarta:
Gramedia.
2
Dawis, A. (2012). The portrait of inspiring indonesian-chinese woman. Jakarta:
BIP-Gramedia
Field, P. & Marck, P. (1994). Uncertain motherhood: negotiating the risks of the
childbearing years. Canada: SAGE Publications.
Fischer, L. R. (1991). Between mothers and daughters. Marriage and
Family Review. 16, 237-248.
Gerungan, W. A. (2004). Psikologi Sosial. Bandung: Refika Aditama
Gould, M. (2011). Socialization in families. The process of socialization, 92-94.
Handayani, C. & Novianto, A. (2004). Kuasa Wanita Jawa. Yogyakarta: LK3IS.
Hidajat, L. Panduan Penyusunan dan Penulisan Skripsi. Jakarta: Unika Atma
Jaya
Kretchmer, J. (2011). Gender Socialization. The process of socialization, 97-107.
Kumar, R. (1999). Research methodology: a step-by-step guide for beginner.
London: Sage Publications.
Meij, L.S. (2009). Perempuan Tionghoa Pasca Kolonial. Jakarta: Obor.
Miller, J.M. (1986). Toward a new psychology of woman. Boston: Beacon Press.
Nasib Kartini Kini. (2012, 21 April). Diakses pada 8 Juli 2012 dari
http://bola.kompas.com/read/2012/04/21/02230296/Nasib.Kartini.Kini.
Kim, J.M. (2003). Structural family therapy and its implication for asian american
family. The Family Journal, 11, 388-391.
Komunikasi pribadi, dilakukan pada tanggal 9 April 2011.
Komunikasi pribadi, dilakukan pada tanggal 12 April 2011.
Komunikasi pribadi, dilakukan pada tanggal 22 November 2011.
3
Lan, T.J. (2005, Mei). Chinese studies and identity building: Dimanakah Tempat
Untuk Studi tentang ‘Orang Cina di Indonesia’?. Makalah disampaikan dalam
Seminar Atma Jaya ‘Chinese Studies and Identity Building”, Jakarta 10 Mei
2005.
Lim, S.G. (1996). Among the white moonfaces: memoirs of an asian american
woman. Singapura: Times Editions-Marshal Cavendish.
Newman, B.M. & Newman, P. (2012). Development through life: a psychosocial
approach. California: Wadsworth.
Nurrachman, N. & Bachtiar, I. (Ed). 2011. Psikologi Perempuan: Pendekatan
Kontekstual Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
Psychological readiness to motherhood. (2010, 1 September). Diakses pada
tanggal 5 Juli 2012 dari http://socyberty.com/psychology/psychological-
readiness-to-motherhood/
Poerwandari, K. (2008). Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku
Manusia. Jakarta: LP3UI.
Risman, B.J. (2004). Gender as a social structure: theory wrestling with activism.
Gender & Society, Vol. 18 No. 4, 429-450.
Sadli, S. (2010). Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan.
Dalam Bachtiar, I. (Ed.). Jakarta: Kompas.
Santrock, J. (2008). Life-span development (10th edition). Sage Publication:
California.
Shelley, J (Eds.). (2007). An introduction to the social psychology of gender. Vol.
24, 1-18.
Sroufe, L., et al. (1996). Child development: it’s nature and course. Mc-Graw
Hill: New York.
4
Surrey, J.L. (1985). Self-in-relation: a theory of woman development. Diakses
pada tanggal 8 Juli 2012 dari
http://www.wcwonline.org/pdf/previews/preview_13sc.pdf
Sidartha, M. (1987). The making of indonesian chinese woman. Leiden: KITLV
Press.
Tan, M.G. (2008). Etnis Tionghoa di Indonesia: Kumpulan Tulisan. Jakarta:
Yayasan Obor.
Weskott, M. (1989). Female relationality & the idealized self. The American
Journal of Psychoanalysis, Vol.49, No.3.
West, C. & Zimmerman, D.H. (1987). Doing gender: gender and society. Diakses
pada 13 November 2011 dari http://gas.sagepub.com/content/1/2/
Wibowo, S. (Ed.). (2009). Manusia: Teka-teki yang Mencari Solusi. Yogyakarta:
Penerbit Kanisius.
Yayasan Jurnal Perempuan. (2001). Jurnal Perempuan No. 16: Ibu dan Anak
Perempuan. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
Yayasan Jurnal Perempuan. (2001). Jurnal Perempuan No. 20: Perempuan dan
Spiritualitas. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Yayasan Jurnal Perempuan. (2001). Jurnal Perempuan No. 22: Perempuan dalam
Perkawinan. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.