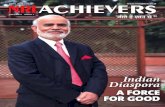POLITIK IDENTITAS DIASPORA MINANG DALAM KARYA
-
Upload
universitasnegerimalang -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of POLITIK IDENTITAS DIASPORA MINANG DALAM KARYA
POLITIK IDENTITAS DIASPORA MINANG DALAM KARYA-KARYA PARAPERUPA KELOMPOK JENDELA DI YOGYAKARTA
TAHUN 2000-2010
HariyantoJurusan Seni dan Desain, Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang
AbstrakPemilihan topik artikel ini didasarkan padasuatu fakta bahwa beberapa kelompok perupaasal Minang termasuk Kelompok Jendela telahberhasil menduduki peringkat atas dalamreputasi mereka sebagai perupa. Para perupaMinang sebagai kaum diaspora telah menunjukkanidentitasnya sebagai perupa dengan karya yangberbeda dengan kelompok lainnya. Tujuan daripenulisan artikel ini ingin mengetahui:politik identitas dan diaspora; perupa Minangdi Yogyakarta; dan politik identitas dalamkarya-karya Kelompok Jendela. Artikel inimembahas: politik identitas dan diaspora;diaspora Minang dalam seni rupa kontemporerYogyakarta; politik identitas dalam karya-karya seni rupa Kelompok Jendela.Kata kunci : politik identitas, diaspora,Minang.
I. Pendahuluan
Perkembangan seni rupa kontemporer Indonesia era
tahun 2000-an ditandai dengan munculnya perupa-perupa muda
di forum internasional baik dalam biennale-biennale
internasional, artfair, maupun di balai-balai lelang. Karya-
karya perupa Indonesia banyak mendapat apresiasi dari
para pengamat internasional dan juga diminati oleh para
kolektor dengan nilai yang tinggi. Para perupa asal
Sumatera Barat yang merantau ke Jawa sebagian besar
menetap di Yogyakarta untuk mengembangkan karir. Mereka
membentuk organisasi Komunitas Seni Sakato sebagai wadah
untuk berkomunikasi sesama perupa Minang di perantauan. Di
dalam komunitas besar itu terdapat beberapa kelompok kecil
perupa seperti Kelompok Jendela, Kelompok Genta, Kelompok
Semoet, dan lain-lain. Kelompok Jendela merupakan kelompok
perupa pertama dari para perupa Minang yang telah berhasil
di forum internasional.
Para perupa Kelompok Jendela menciptakan gaya visual
yang berbeda dengan gaya dominan yang berkembang pada era
pasca reformasi. Pada era pasca reformasi para perupa
kontemporer di Yogyakarta dipengaruhi oleh suasana sosial-
politik yang berkembang pada saat itu. Ekspresi seni rupa
yang tampak dalam gaya visual para perupa merupakan
cerminan kehidupan sosial-politik nasional. Wacana sosial-
politik menjadi tema dominan dalam seni rupa kontemporer
Yogyakarta pada akhir tahun 1990-an. Para perupa Kelompok
Jendela tidak mengikuti arus yang dominan, mereka justru
menciptakan gaya visual yang menghindari tema-tema sosial-
politik disebabkan oleh pertimbangan pengalaman historis
dan budaya mereka. Gaya visual perupa etnis Minang ini
kemudian berpengaruh terhadap kelompok-kelompok perupa
Minang yang lain seperti Kelompok Genta dan Kelompok
Semoet. Keberadaan Kelompok Jendela yang menjadi
representasi identitas Minang kini menjadi setara dengan
gaya yang dominan di Jawa (Yogyakarta). Gaya non-politis
yang dikembangkan oleh perupa Kelompok Jendela ini pada
akhirnya dapat dipahami sebagai bentuk politik identitas
perupa etnis Minang di perantauan.
Keberhasilan Kelompok Jendela menembus forum
internasional dan menjadi incaran para kolektor merupakan
fenomena yang menarik. Kelompok Jendela merevitalisasi
nilai-nilai tradisi Minang dengan bahasa visual yang
berbeda dengan gaya yang sedang dominan dalam seni rupa
kontemporer Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Identitas
budaya Minang yang tersirat dalam karya Kelompok Jendela
menjadi kekuatan yang dapat menjadi wacana alternatif dari
wacana yang berkembang saat ini. Mereka menyadari perlunya
identitas budaya sebagai kekuatan untuk bersaing di forum
global sehingga dapat mensejajarkan diri dengan perupa
dari komunitas lain maupun perupa internasional. Para
perupa Kelompok Jendela telah berhasil memainkan politik
identitas sehingga dapat menemukan identitas visual yang
saat ini berpengaruh dalam seni rupa kontemporer
Indonesia.
Politik identitas yang dikembangkan oleh para perupa
Kelompok Jendela melalui karya-karya yang dihasilkan
mereka merupakan fenomena yang menarik untuk dibahas. Daya
tarik mereka tidak hanya dari aspek visualnya saja tetapi
juga karena para perupa itu mewakili kelompok etnis Minang
yang memiliki relasi historis dengan sejarah Jawa.
Kelompok perupa Minang itu juga memiliki tradisi merantau
sehingga keberadaan mereka dapat dikategorikan sebagai
kaum diaspora yang pada saat ini sudah menjadi fenomena
global. Tulisan ini akan membahas tentang : politik
identitas dan diaspora; diaspora Minang dalam seni rupa
kontemporer Yogyakarta; dan politik identitas dalam karya
seni rupa Kelompok Jendela.
II. Politik Identitas dan Diaspora
Politik identitas adalah tindakan politis untuk
memajukan kepentingan anggota dari suatu kelompok yang
anggotanya memahami diri mereka sendiri mendapat tekanan
disebabkan karena identitas yang sama dan termarjinalkan
(seperti ras, etnisitas, agama, jender, orientasi seksual.1
Politik identitas sebagai sebuah mode pengorganisasian
sangat dekat berhubungan dengan gagasan bahwa beberapa
kelompok sosial telah mengalami tekanan yaitu bahwa
identitasnya sebagai seorang perempuan, atau sebagai
penduduk asli, misalnya membuat orang secara khusus
menjadi rawan terhadap imperialisme budaya (termasuk
penstereotipan, penghapusan, atau perampasan dari suatu
identitas kelompok), kejahatan, eksploitasi, marjinalisasi
atau tidak memiliki kekuasaan.2
1 Esiklopedia Wikipidia,http://en.wikipedia.org/wiki/Identity_politics , diakses 7September 2011.2 ? Young Iris Marion, Justice and the Politics of Difference (Princeton:Princeton University Press, 1990)
Eleanor Heartney menyatakan bahwa biennale seni rupa
kontemporer sebagai forum untuk presentasi karya seni rupa
yang berkembang luas saat ini sebagai cara untuk mereduksi
isu-isu sosial yang kompleks menjadi sebuah politik
identitas. Politik identitas menghindari determinasi
sosial ekonomi seperti kelas, agama, dan nasionalitas,
sebaliknya menyajikan model reduktif dari masyarakat
seperti pertempuran antara pihak yang tertekan dengan
pihak yang menekan.3
Masyarakat etnis Minang memiliki tradisi merantau
keluar daerah dan keluar negeri untuk memperbaiki kualitas
hidup mereka. Istilah diaspora berasal dari bahasa Yunani
kuno yang artinya, “penyebaran atau penaburan benih”
digunakan untuk merujuk kepada bangsa atau penduduk etnis
manapun yang terpaksa atau terdorong untuk meninggalkan
tanah air etnis tradisional mereka; penyebaran mereka di
berbagai bagian lain dunia, dan perkembangan yang
3 Eleanor Heartney, "Identity politics at the Whitney -Multiculturalism Explored in Whitney Museum of Modern Art's 1993 Biennial ArtExhibition" Art in America. (Mei, 1993). 166.
dihasilkan karena penyebaran dan budaya mereka.4 Makna asli
dari kata “diaspora” digunakan untuk merujuk secara khusus
kepada penduduk Yahudi yang dibuang dari Yudea pada 586 SM
oleh Babel, dan Yerusalem pada 135 M oleh Kekaisaran
Romawi. Istilah ini digunakan berganti-ganti untuk merujuk
kepada gerakan historis dari penduduk etnis Israel yang
tersebar, perkembangan budaya penduduk itu, atau penduduk
itu sendiri.
Kini istilah diaspora berlaku bagi semua etnis yang
hidup di luar tanah asalnya. Setelah era kolonial banyak
para imigran dari bekas jajahan Inggris melakukan migrasi
ke Inggris atau ke negara Barat lainnya. Sebagian di
antara imigran dari bekas negara jajahan Inggris itu
adalah kaum intelektual poskolonial. Para teoritisi
poskolonial pada umumnya berbicara tentang hubungan antara
budaya asal mereka (etnik/tradisi) dengan budaya Barat.
Edward Said membicarakan tentang stereotip pandangan orang
Barat terhadap orang Timur yang masih bersifat kolonialis
dan Orientalis, yang menganggap orang Timut sebagai
4 http://en.wikipedia.org, diakses 7 September 2011
”other” dan inferior.5 Stuart Hall menyoroti tentang
perlakuan orang Barat terhadap orang kulit hitam Afrika
dengan mengungkap representasi visual (sinema dan
fotografi) tentang orang hitam yang diproduksi budaya
Barat.6 Homi Bhabha membahas tentang budaya hibrida yang
dihasilkan oleh kaum diaspora.7
Identitas menjadi penting bagi kaum diaspora, karena
pengalaman sebagai kaum “terusir” yang mengalami krisis
identitas layak bicara tentang pengalamannya melalui
representasi. Karena menurut Stuart Hall identitas tidak
ditetapkan di luar, tetapi di dalam representasi.8 Terdapat
dua cara berpikir dalam melihat identitas budaya. Yang
pertama, mendefinisikan identitas budaya dalam pengertian
sebagai satu budaya bersama, sejenis suatu diri kolektif
5 Edward Said, Orientalism, (New York; Vintage Books, 1978),31-48.
6 Stuart Hall, “The Spectacle of ‘Other’”, dalam StuartHall, Representation : Cultural Representation and Signifying Practice (London:Sage, 2003). 223-290.
7 Homi K. Bhabha, The Location of Culture (New York: Routledge,2005). 200.
8 Stuart Hall, “Cultural Identity and Diaspora”, dalam,Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth; dan Tiffin, Helen, The Post-Colonial Studies Readers, edisi ke-2 (New York: Routledge, 2006).Maret 2011. 435-438.
yang benar, tersembunyi di samping banyak lainnya, lebih
ditekankan pada “diri-diri” yang superfisial atau
artifisial, yang mana masyarakat dengan sejarah dan
leluhurnya selalu dipegang pada umumnya. Dalam pengertian
ini identitas budaya kita mencerminkan pengalaman historis
umum dan kode-kode budaya bersama, yang menentukan kita
sebagai “satu masyarakat”, dengan kerangka berpikir dan
makna yang stabil, tidak berubah dan berkelanjutan, di
bawah bagian-bagian yang sedang berubah dari sejarah
aktual kita.
Cara melihat identitas yang kedua adalah dalam posisi
mengakui adanya banyak kesamaan, tetapi terdapat juga
bagian kritis dari perbedaan yang mendalam dan signifikan
yang menentukan “apakah kita telah menjadi”. Persoalan
identitas budaya menurut pengertian yang kedua ini adalah
persoalan “menjadi” sebagaimana “mengada”. Ini menjadi
milik masa depan juga milik masa lampau. Identitas budaya
datang dari suatu tempat, mempunyai sejarah. Tetapi
seperti setiap apapun yang mempunyai sejarah, mereka
mengalami transformasi yang konstan.9
Istilah “diaspora” menunjuk pada orang-orang yang
tidak hidup di tanah-airnya sendiri, orang-orang yang
terusir (Yahudi, Armenia dan Yunani), apapun sebab,
jumlah, organisasi, atau lamanya pengusiran. Pada
kesempatan lain istilah ini digunakan untuk menunjuk
sekelompok atau koloni ekspatriat, pelarian, migran elite,
pengusaha asing, pengungsi, buruh migran, pelintas-batas,
pekerja tamu, dan sekelompok etnik minoritas.10 Berdasarkan
pendapat Tololyan maka para perantau dari Minang dapat
dikategorikan sebagai kaum diaspora yang bekerja di daerah
lain dengan budaya yang berbeda.
Cohen mengkategorikan kaum diaspora ke dalam
beberapa jenis seperti: “diaspora korban” yang dialami
9 Stuart Hall, “Cultural Identity and Diaspora” dalam J.Rutherford , ed, Identity:Community, Culture, Difference (London: Lawrenceand Wishart, 1990), 222-237.
10 Khachig Tololyan, “Armenian Diaspora”, dalam MelvinEmber,Carol R. Ember,Ian Skoggard, ed, Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and RefugeeCultures Around the World, (New York: Springer Science+Business MediaInc., 2005) 35-36.
oleh misalnya bangsa Yahudi, Afrika dan Armenia. “Diaspora
buruh”, yang dilakukan oleh buruh kontrak India.
“Diaspora perdagangan” yang dilakukan oleh bangsa Cina dan
Libanon. “Diaspora imperial” atau kekaisaran yang
dilakukan oleh bangsa Inggris, dan “Diaspora kultural”
yang dijalani oleh bangsa Karibia di luar tanah airnya.11
Para perantau Minang di Jawa sebagian besar berdagang
karena mereka memang memiliki etos dagang yang tinggi. Di
Yogyakarta para perantau asal Minang sebagian besar adalah
mahasiswa, intelektual, dan pekerja seni. Perupa-perupa
asal Minang bergabung dalam komunitas seni Sakato yang
jumlah anggotanya lebih dari seratus orang. Dengan
menggunakan kategori dari Cohen maka etnis Minang yang
merantau ke Jawa dapat dikategorikan sebagai ”diaspora
perdagangan” dan ”diaspora kultural”.
Kasus diaspora yang sering menimbulkan masalah sejak
zaman kolonial adalah diaspora Tionghoa yang sering
disebut dengan istilah peranakan. Sejarah sosial dari kaum
11 ? R. Cohen, Global diasporas: An introduction. (London: UCL Press,1997). x.
peranakan (diaspora) Tionghoa di Indonesia sudah banyak
ditulis, tetapi dalam bidang seni khususnya seni rupa
masih sedikit. Para kolektor dan pemilik galeri kebanyakan
berasal dari kaum peranakan. Kini di saat seni kontemporer
Indonesia berkembang sebagai bagian dari perkembangan di
Asia-Pasifik, peran mereka juga cukup signifikan baik
sebagai donatur/kolektor, seniman, kurator maupun pemilik
galeri. Peran kaum diaspora Tionghoa ini dalam mendorong
perkembangan seni rupa kontemporer di Indonesia telah
diangkat menjadi objek penelitian yang menarik untuk
desertasi doktor.12 Penelitian yang dilakukan Djatiprambudi
membuktikan bahwa mengkoleksi atau mengapresiasi karya
seni rupa sebagai bagian penting yang mendukung
kelangsungan hidup seni rupa dapat berfungsi sebagai
representasi identitas kelompok etnis Tionghoa. Para
perupa, kolektor, kurator, dan pemilik galeri yang berasal
dari keturunan Tionghoa telah berhasil memainkan politik
identitas dalam bidang seni rupa termasuk di dalamnya
12 ? Djuli Djatiprambudi, ”Komodifikasi Seni Rupa KontemporerIndonesia”, Jurnal Panggung Vol. 20, No. 1 (Januari-Maret 2010),45-61.
perdagangan barang seni. Komunitas diaspora Tionghoa di
Indonesia menurut Cohen termasuk ”diaspora perdagangan”
dan dengan berhasilnya memainkan politik identitas di
bidang seni rupa maka mereka layak disebut ”diaspora
kultural”.
III. Perupa ”Diaspora” Minang dalam Seni rupa KontemporerYogyakarta
Para perupa etnis Minangkabau dari Sumatera Barat
yang belajar di Jawa dan menetap di sana adalah kaum
diaspora yang memiliki ikatan kultural dengan tanah
asalnya. Karakteristik orang Minang yang positif adalah
berwatak egaliter, memiliki harga diri yang tinggi, suka
berdebat, dan yang menonjol adalah suka berdagang.13 Orang
Minang adalah pemeluk agama Islam yang taat dan pemegang
adat tradisi yang kuat. Orang Minang memiliki sifat
“dinamis“ karena suka berpindah tempat, dan berjiwa
wirausaha, mereka juga “modernis“ dalam pendidikan,
pekerjaan, pandangan politik, dan kesadaran media, tetapi
dalam waktu yang sama mereka bisa “konservatif“ karena13 Syamdani, PRRI, Pemberontak atau Bukan?, (Yogyakarta:Media
Presindo, 2008), 14-33.
berpegang kuat pada tradisi.14 Orang Minang berpandangan
bahwa Alam (Minangkabau) merupakan pusat, jantung,
sementara keberadaan rantau adalah untuk memperkaya Alam.15
Ciri-ciri yang dikemukakan oleh para penulis di atas
menunjukkan bahwa etnis Minang memiliki semangat kolektif
yang tinggi sehingga mampu bertahan hidup di perantauan
untuk memperbaiki nasib mereka dan juga untuk meningkatkan
martabat etnis mereka di mata etnis yang lain.
Dalam budaya Minang yang sarat dengan tradisi lisan
dikenal dengan pepatah-petitih, peribahasa, kata-kata
bijak yang mengandung filosofi yang tinggi. Kalimat “Alam
terkembang jadi guru“ merupakan kata-kata bijak yang
filosofis mengandung nilai edukasi dan moral yang tinggi.
Filosofi ini masih diyakini mampu menjadi semacam pelita
bagi para perantau Minang. Peribahasa “Di situ bumi
dipijak, di sana langit dijunjung“ menunjukkan bahwa orang
Minang dapat menyesuaikan diri dengan daerah yang baru.
14 Tsuyoshi Kato, Adat Minangkabau dan Merantau dalamPerspektif Sejarah, (Jakarta: Balai Pusaka,2005).167.
15 Syamdani. 14-33.
Masyarakat Minang di perantauan membentuk komunitas
yang tujuannya untuk sarana berkomunikasi dan
menjadikannya sebagai media untuk memelihara tradisi bagi
kepentingan identitas budaya mereka. Menurut Giddens
tradisi adalah medium identitas, apakah secara pribadi
atau kolektif, identitas mengasumsikan makna tetapi
identitas juga mengasumsikan proses konstan dari
rekapitulasi dan reinterpretasi. Identitas adalah
penciptaan konstansi dalam perjalanan waktu, yang
menghubungkan masa lalu dengan masa depan.16 Tradisi adalah
orientasi ke masa lalu, bahwa masa lalu memiliki pengaruh
besar, atau tradisi memiliki pengaruh besar terhadap masa
sekarang.17 Tradisi terkait dengan memori, terutama memori
kolektif (Giddens, 2003, 47).18 Pendapat Giddens ini sesuai
dengan karakter etnis Minang di perantauan yang masih
menjunjung tinggi tradisi dan menjadikan masalalu mereka
16 ? Anthony Giddens, Masyarakat Post-Tradisional,(Yogyakarta:IRCiCoD, 2003), 47, terjemahan Ali Nur Zaman, buku asli, Living in Post-Traditional Society, (Cambridge: Polity Press, 1994).
17 Giddens, 47.18 Giddens, 47.
sebagai sumber penciptaan dan pengembangan wacana dalam
berkesenian terutama di bidang seni rupa.
Pada era Orde Baru pemerintah mendorong pencarian
identitas nasional atau kepribadian nasional terhadap
kreasi seni melalui sumber tradisi. Unsur-unsur tradisi
terlihat hanya kulit luarnya saja yang menempel pada
bentuk-bentuk seni lukis modern. Karya-karya seni lukis
modern menjadi terkucil dari masyarakatnya dan dianggap
sebagai bentuk depolitisasi seni yang dilakukan oleh
pemerintah. Gerakan Seni Rupa Baru dan beberapa kelompok
pendukungnya melakukan koreksi dengan menciptakan karya-
karya alternatif yang kembali kepada nilai kemanusiaan.19
Karya alternatif yang bernilai kemanusiaan ini kemudian
menjadi arus utama dalam seni rupa kontemporer Indonesia.
Awal tahun 1990-an seni rupa kontemporer mulai
mendapat perhatian dari para perupa, kurator, galeri,
kolektor, balai lelang, dan institusi seni lainnya. Seni
rupa kontemporer berkembang pesat bersamaan dengan
19 Agus Burhan, “Kelahiran dan Perkembangan Gerakan SeniRupa Baru Indonesia“, Jurnal Panggung Vol. 20, No. 1 (Januari-Maret 2010). 1-23.
munculnya komodifikasi seni lukis di pasar internasional.
Seni lukis menjadi tanda simbolik yang dipercaya dapat
memproduksi makna representasi dalam dimensi sosial-
budaya. Dalam arti tertentu seni lukis dijadikan sebagai
tanda untuk membangun simbol sosial yang terkait dengan
kelas, status, kuasa, dan resistensi. Komodifikasi seni
rupa merupakan ruang sosio-kultural elite ekonomi dalam
upaya membangun representasi identitas etnik minoritas
dalam konstruksi kebudayaan kontemporer Indonesia.20 Jika
pada era Orde Baru pembentukan identitas nasional
ditekankan oleh pemerintah melalui institusi dan
aparaturnya, maka pada era reformasi yang berperan dalam
membentuk identitas budaya adalah institusi seni non-
pemerintah. Para kurator, kolektor, dan pemilik galeri
dari kalangan etnis Tionghoa berperan utama sebagai
konsumen atau apresiator seni rupa yang tidak jarang
mempengaruhi produksi seni rupa. Komunitas perupa Minang
yang didukung organisasi Sakato telah berperan sebagai
institusi produksi seni rupa yang melayani konsumen seni
20 Djatiprambudi, 45-61.
rupa. Perupa-perupa Minang yang telah berhasil sebagai
perupa internasional tentu saja telah bekerjasama dengan
para kurator dan pemilik galeri yang sebagian besar adalah
kaum diaspora Tionghoa.
Menurut Kahin diaspora Minang baru terjadi secara
besar-besaran setelah meletusnya peristiwa PRRI. Orang
Minang memiliki ajaran kultural yang mendorong para pemuda
untuk merantau yaitu mengalahkan “rantau nan batuah“ yang
memiliki arti kemenangan sosial di kampung.21 Para perupa
Minang yang belajar di Yogyakarta banyak di antara mereka
memilih menetap di kota itu untuk mengembangkan karir.
Para perupa asal Minang itu kemudian membentuk Komunitas
Seni Sakato yang diikuti dengan pembentukan kelompok
perupa yang lebih kecil seperti Kelompok Jendela. Etos
diaspora para perupa Minang di rantau yang penuh semangat
dan ulet merupakan bentuk praktek kultural mereka untuk
menaklukan “rantau nan batuah“ khususnya dalam art wold
(medan sosial seni) di Yogyakarta.
21 Audrey Kahin, Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998 (Jakarta: Yaysan Obor Indonesia, 2005), xv.
IV. Politik Identitas dalam Karya-karya Perupa Kelompok
Jendela
Identitas seni rupa kontemporer perupa Minang di
Yogyakarta seperti ’Kelompok Jendela’, ’Kelompok Genta’
dan ’Kelompok Semoet’ menunjukkan kekhususannya sendiri
dibanding identitas seni rupa kontemporer Yogyakarta pada
umumnya. Untuk melacak jejak identitas seni rupa oleh
perupa Minang maka dapat kita lihat karakter orang Minang
terutama para sastrawan dan perupa termasuk juga para
politisi asal Minang yang pernah jaya pada masa lampau.
Watak sastrawan asal Minang seperti Sutan Takdir
Alisyahbana, Abdul Muis, Hamka, Chairil Anwar, Usmar
Ismail dan Asrul Sani adalah berpikir merdeka dan berjiwa
pemberontak sehingga mereka berhasil di tingkat nasional
pada era Pujanga Baru.22 Karakteristik para politisi Minang
seperti Tan Malaka, Hatta, Sjahrir, Natsir, dan lain-lain
juga demikian, hal ini berbeda dengan karakteristik
22 Pernyataan Ketua Dewan Kesenian Sumatera Barat Dr HarrisEffendi Thahar pada seminar ”Menumbuhkembangkan Bakat dan KemauanMenulis Karya Sastra di Minangkabau”, lihat, Surat kabar Kompas,Minggu (16 November 2008), 12.
masyarakat Indonesia lainnya yang patrimonial dan feodal
sehingga menghambat demokrasi.23
Sejarah seni rupa modern Minang dimulai dengan
kemunculan Wakidi orang Jawa yang lahir di Palembang kira-
kira tahun 1889. Pada tahun 1893 ia belajar di sekolah
guru Bukit Tinggi yang merupakan satu-satunya di Sumatera
pada saat itu. Karena bakat artistik Wakidi yang menonjol,
ia dikirim oleh guru Belanda untuk belajar melukis kepada
pelukis Belanda Van Dijk di Semarang. Setelah belajar
melukis kepada Van Dijk kemudian Wakidi mengajar seni di
Bukit Tinggi hingga tahun 1950-an.24 Wakidi banyak
23 Zulfikri Suleman dan Kurniawan Junaedhie. ed, Demokrasiuntuk Indonesia: pemikiran politik Bung Hatta (Jakarta: Penerbit BukuKompas, 2010) , 53. Masyarakat lain di Indonesia dalam pikiranorang Minang lebih diarahkan ke orang-orang Jawa. Sepertidinyatakan Beckmann, musuh bersama orang Minang ketika zamankolonial adalah Belanda, sedangkan pada masa PRRI adalah orangJawa. Lihat, Franz Beckmann, dan Keebet von Benda. ”Ambivalentidentities: decentralization and Minangkabau politicalCommunities”, dalam Henk Schulte Nordholf, Geert Arendt vonKlinken, dan Gerry von Klinken. Renegotiating boundaries: local polities inPost-Soeharto Indonesia (Leiden: KITLV Press, 2007) , 417-442.
24 Claire Holt, Art in Indonesia, Continuities and Change, IthacaNew York: Cornell University Press, 1967. Lihat edisiterjemahan RM. Soedarsono, Melacak Jejak Perkembangan Seni diIndonesia (Bandung, Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia,2000). 507-532.
menghasilkan lukisan pemandangan alam dengan objek
panorama alam Minangkabau. Karya-karya Wakidi biasa
disejajarkan dengan karya-karya Abdullah Suriosubroto dan
Pirngadi yang tergolong dalam mooi Indie.
Perupa Minang setelah Wakidi baru muncul pada masa
revolusi yaitu Oesman Effendi dan Zaini yang menjadi
anggota SIM di Yogyakarta. Oesman Effendi, Zaini, dan
Nashar dikenal sebagai perupa (pelukis) Minang yang
menganut gaya non-representatif atau non-realis. Tiga
perupa Minang ini pada tahun 1950-an aktif di Badan
Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) sebuah badan non-
politik yang disubsidi oleh pemerintah. BMKN dinilai
kurang nasionalis dan condong pada ideologi liberal, sehingga
menjadi pesaing Lekra yang mendukung ideologi komunis dan
Lembaga Kesenian Nasional yang mendukung ideologi
nasionalis. Terdapat seorang perupa Minang yang menjadi
anggota Pelukis Rakyat yaitu Itji Tarmizi. Karya Tarmizi
Lelang Ikan (1958-1960), sebuah lukisan gaya realis termasuk
dalam koleksi Soekarno.25
25 Seno Joko Suyono, “Potret Diri Sang Pelukis Rakyat”,Majalah Tempo interaktif, 10 Desember 2001, online,
Pemikiran liberal para perupa BMKN ternyata sejajar
dengan pikiran Sutan Takdir Alisyahbana seorang tokoh
Pujangga Baru yang pada tahun 1935 memulai Polemik
Kebudayaan dengan melontarkan gagasan yang berupa ajakan
untuk mengubah masyarakat Indonesia yang ’statis’ menjadi
sebuah masyarakat yang ’dinamis’ dengan mengadopsi sikap-
sikap dan teknik-teknik Barat.26 Pandangan Sutan Takdir
Alisyahbana berseberangan dengan pandangan para
intelektual Jawa yang menghendaki agar bangsa Indonesia
tidak melupakan budaya tradisi. Sutan Takdir menganggap
para pemikir Jawa bersikap anti-intelektualisme, anti-
materialisme, dan anti-individualisme karena menghendaki
kembali kepada kepunyaan yang lama.27
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/3001/12/10/SR/mbm.20011210.SR86208.id.html. diakses28 Januari 2011.
26 Holt, 314.27 Tim redaksi majalah Tempo. ”Polemik kebudayaan, sesudah
50 tahun”, Majalah Tempo interaktif, 17 Mei 1986 http://majalah.tempointeraktif.com /id/ arsip /1986/05/17/ KL/mbm. 19860517.KL33483.id.html, diakses 28 Januari 2011. Lihat juga, KurieSuditomo, SJS. “Gaya Tuan STA Berpolemik”, Majalah Tempointeraktif (25 Februari, 2008), online,http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/ 2008 /02/25/LYR/mbm.20080225.LYR126442.id.html diakses 28 Januari 2011.
Surat Kepercayaan Gelanggang yang dimuat
dalam majalah Siasat, 22 Oktober 1950 dianggap mewakili
pendirian, semangat, dan sikap estetik Angkatan ’45 yang
menerima pengaruh Barat merupakan kelanjutan dari
pandangan Sutan Takdir Alisyahbana. Konseptor dari surat
kepercayaan ini adalah Asrul Sani seorang sastrawan
Minang. Surat Kepercayaan Gelanggang dimaksudkan sebagai
reaksi atas publikasi Mukadimah Lekra (Lembaga Kebudayaan
Rakyat) yang dicetuskan 17 Agustus 1950.28 Kecenderungan ke
arah pembaratan dan universalisme dalam jangka waktu
tertentu merupakan ciri penulis non Jawa yang merantau ke
Jawa dan kehilangan akar budayanya.29
Karakteristik orang Minang yang tercermin dalam sikap
para sastrawan dan perupa bisa menjadi petunjuk dalam
melihat sikap dan kreasi para perupa asal Minang di
Yogyakarta. Pandangan budaya para senior yang dinamis,
modernis, universal, dan anti-tradisi sejajar dengan
28 Maman S. Mahayana, “Asrul Sani Konseptor SuratKepercayaan Gelanggang”,http://mahayana-mahadewa.com/2010/10/07/asrul-sani-konseptor-surat-kepercayaan-gelanggang/ diakses 28 Januari 2011.
29 Denys Lombard. Nusa Jawa Silang Budaya: Batas-batas Pembaratan(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) , 216-246.
keyakinan orang Minang dalam memeluk Islam yang modern.
Pilihan terhadap seni rupa non-representatif (abstrak)
sesuai dengan semangat modernisme yang menuntut estetika
universal dan larangan Islam terhadap penggambaran mahluk
hidup. Para perupa Muslim beranggapan bahwa seni abstrak
adalah sangat cocok bagi jiwa Islami.30
Perupa Minang di Yogyakarta yang berhasil diterima
oleh peminat seni rupa kontemporer di dalam dan luar
negeri antara lain adalah para anggota Kelompok Jendela,
Kelompok Genta dan Kelompok Semoet. Ketiga kelompok perupa
asal Minang ini dapat dikatakan menonjol perannya dalam
perkembangan seni rupa kontemporer Yogyakarta.
Keberhasilan mereka dalam art world seni rupa kontemporer
nasional maupun di kawasan Asia disebabkan usaha keras
mereka terutama dalam menampilkan karya yang berbeda
dengan arus utama. Pelopor dari semacam gerakan ini adalah
30 Holt, 319. Hadis Nabi yang berkaitan dengan gambarmisalnya ”Sesungguhnya para malaikat tidak memasuki suatu rumah yang didalamnya ada anjing dan gambar timbul (relief)”. (HR. Ahmad, At Tirmidzidan Ibnu Hibban); dan ”Barangsiapa membuat gambar di dunia, makaia akan dituntut agar meniupkan ruh di dalamnya pada hari kiamat,sedangkan ia bukan orang yang mampu meniupnya” (HR. Ahmad,Bukhari, dan Muslim). Lihat , Mahmud asy-Syafrowi. MengundangMalaikat ke rumah (Yogyakarta : Mutiara Media, 2010), 72-73.
para perupa dari Kelompok Jendela, sedangkan Kelompok
Genta dan Kelompok Semoet mengikutinya dengan gaya yang
tidak jauh berbeda.
Kelompok Jendela.
Kelompok Seni Rupa Jendela dibentuk pada tahun 1996 dengan
anggota yaitu : Handiwirman Saputra, Rudi Mantovani,
Jumaldi Alfi, Yunizar, dan Yusra Martunus. Kelima perupa
ini belajar di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta
dengan program studi yang berbeda-beda: Handiwirman
berpendidikan kriya kayu, Rudi Mantovani dan Yusra
Martunus belajar seni patung, Jumaldi Alfi dan Yunizar
belajar seni lukis. Seni rupa kontemporer Yogyakarta pada
tahun 1990-an terjebak dalam ’seni berkomunikasi’ yang
kontekstual. Karya-karya dari perupa Kelompok Jendela
dianggap sebagai antitesis terhadap corak repesentasional
yang memiliki relasi dengan konteks sosial. Dengan
berbagai cara, mereka membongkar konvensi seni rupa untuk
mewujudkan jargon ’seni tanpa wilayah perbatasan’.31
Handiwirman lahir di Bukittinggi, 1975 adalah perupa
yang paling menonjol dalam Kelompok Jendela banyak
menciptakan seni objek dengan bahan-bahan yang sederhana
seperti spon, plastik, rambut, benang dan sebagainya.
Objek-objek dari bahan sederhana itu dibuat dengan teknik
jahit dan ikat. Bentuk-bentuk objek yang dihasilkan pada
umumnya tidak representasional dan tidak fungsional.
Sebagian objek yang diciptakan Handiwirman dibuat dengan
teknik cetak dengan bahan resin dan ada juga objek yang
berbentuk benda pakai tetapi ukurannya dibesarkan sehingga
menjadi tidak fungsional.
Kepeloporan Handiwirman dalam seni objek ditunjukkan
dalam pameran tunggal Apa Apanya Dong? tahun 2004 di Nadi
Gallery yang banyak mendapat perhatian dari publik seni
nasional. Pada tahun 2004 Majalah Tempo memberi
31 Raihul Fadjri. ”Antitesis Seni Rupa Kontemporer”, MajalahTempo, 08 Mei (2000), http://majalah.tempointeraktif.com/id /arsip/2000 /05 /08 /SR/ mbm.20000508.SR113243.id.html, diakses 31Januari 2011.
penghargaan kepada Handiwirman sebagai salah satu Tokoh
Tahun 2004 yang menjadi penyaji seni terbaik tahun 2004.
Handiwirman tampak menonjol di tengah seni rupa Indonesia
yang didominasi oleh ’ekspresionisme baru’ maupun ’seni
konseptual’. Sebagai antipoda terhadap keduanya, Handiwirman
menggagas lebih tajam, yaitu mempersoalkan dasar-dasar
representasi dan persepsi dalam seni rupa, ia juga
berekspresi lebih gemilang, karena ia mempunyai
keterampilan menggambar dan merakit.32
Jika para perupa pada umumnya mengambil objek dari
kehidupan nyata berupa manusia, binatang maupun benda-
benda, sementara Handiwirman membuat benda-benda dari
bahan sederhana kemudian benda ciptaannya itu dijadikan
objek lukisan. Objek-objek ciptaan Handiwirman kebanyakan
bukan benda pakai maupun benda hias karena bentuknya tidak
berhubungan dengan bentuk nyata, dan visualisasinya juga
tidak dihias secara konvensional dan tidak diberi warna.
32 Tim Tempo , ”Tiga Penguak Tabir”, Edisi KhususMajalah Tempo, (27 Desember 2004); lihat juga, ”Jalan Lain keEstetika”, Majalah Tempo, 27 (Desember 2004), online,http://majalah.tempointeraktif.com/id /arsip/ diakses 31 Januari2011.
Dalam perkembangan seni rupa kontemporer karya-karya
trimatra Handiwirman disebut sebagai seni objek. Objek-objek
hasil ciptaan Handiwirman tidak menampakkan ciri
monumental atau megah seperti karya patung konvensional.
Kebanyakan objek yang dibuatnya hanya menggunakan bahan
sederhana seperti spon, plastik, benang, rambut dan
sebagainya. Seorang pengamat menyebutkan bahwa karya-karya
Handiwirman sebagai ’estetika darurat’.33 Pemberian istilah
darurat ini karena Handiwirman memindahkan objek itu ke
permukaan kanvas yang berukuran besar. Lukisan-lukisan
yang ’mengabadikan’ atau merekam objek ciptaan Handiwirman
ini sepintas mirip lukisan alam benda yang realis,
sehingga Hendro Wiyanto mengelompokkan karyanya ke dalam
istilah pseudo still life.34
Objek-objek yang telah diciptakan oleh Handiwirman
yang kemudian menjadi model (objek) dalam lukisan-
lukisannya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa seri
33 Alia Swastika. ”Melampaui Estetika Darurat”,dalamhttp://aliaswastika.multiply.com/reviews/item/111, diakses 4Februari 2011.
34 Hendro Wiyanto. ”Pseudo Still Life”, pengantar kuratorialpameran Pseudo Still Life, di Galeri Semarang, 30 April – 14 Mei 2005.
yaitu; seri mental, seri salon, seri sofa, dan seri
Tuturkarena. Pada seri mental obyek dibuat dari bahan
segumpal lempung hitam, segumpal kapas putih dan seutas
benang merah. Sesuai dengan karakter bahan maka gumpalan
lempung hitam selalu ditempatkan di bagian bawah,
sedangkan gumpalan kapas putih menempel di atasnya. Karya
Handiwirman yang tergolong pada seri salon, bahan yang
digunakan untuk membuat objek terdiri dari spon kuning dan
oranye, kapas putih, kain merah, dan benang merah. Bentuk-
bentuk objek yang diciptakan berciri non figuratif, non
geometrik, dan non representatif. Gumpalan spon sebagai
bentuk utama dibuat dari lembaran spon yang dijahit dengan
benang, sedangkan gumpalan kapas putih ditempelkan di
bagian tengah atau bagian atas gumpalan spon.
Gambar 1: Handiwirman, a. Sealer, 2009, objek 3D ; b.Menahan, 2007, lukisan akrilik (Sumber: a. forum,detik.com;
b. artvalue.com)
Objek yang tergolong dalam seri sofa lebih kongkrit
dibanding dengan seri-seri yang lain, sofa ditampilkan
secara nyata dengan bahan serat fiber dan resin,
sedangkan objek mirip manusia atau boneka yang tergolek di
atas sofa tidak nyata. Karya Handiwirman yang berjudul
Sofa & Pose No. 1, 2 & 3, (2004) merupakan contoh dari objek
dan lukisan yang dipamerkan secara bersamaan. Pada bagian
depan berjajar tiga sofa dengan masing-masing terdapat
semacam boneka yang posenya berbeda. Pada dinding di atas
jajaran sofa dipajang tiga lukisan yang masing-masing
terdapat objeknya yang nyata hasil karya Handiwirman.
Gambar 2 : Handiwirman, Sofa & Pose No. 1, 2 & 3, 2004 (Sumber: rogueart.asia)
Objek-objek pada seri Tuturkarena dibuat dari bahan
utama resin, cat akrilik, logam, kain, dan rambut.
Karakter dari objek dalam seri ini lebih padat dan keras
dengan bentuk dasar agak bulat-lonjong warna dominan
putih. Pada bentuk-bentuk objek dalam seri ini di
antaranya ada yang digurat bagian atasnya sehingga
hasilnya mengkerut ke dalam, pada objek yang lain disumpal
dengan kain secara horisontal seperti bentuk mulut.
Terdapat objek dalam seri ini yang diberi judul dengan
bahasa Jawa Merem dan Mingkem (2008). Pada tahun 2011
Handiwirman menyelenggarakan pameran tunggal dengan tajuk
No Roots, No Shoots di Nadi Gallery Jakarta. Semua karyanya
berupa instalasi dari berbagai material, semua karyanya
diberi judul berseri Tak Berakar, Tak Berpucuk-no 1 – no 7. Tajuk
pameran ini diambil dari pepatah Melayu termasuk Minang
yang berbunyi Ke atas tak berpucuk ke bawah tak berakar, di tengah-
tengah digerek kumbang. Pepatah ini bermakna kutukan atau
sumpah bagi orang yang tidak menepati janji, misalnya
tidak selamat hidupnya jika melanggar janji tersebut.
Gambar 3 : Tak berakar tak berpucuk No. 1 (Sumber: pasarseni.indonesiakreatif.net)
Rudi Mantovani lahir di Padang 1973, belajar seni
patung di Institut Seni Indonesia, karya yang dihasilkan
seni patung, seni objek, instalasi, dan seni lukis. Karya
yang dihasilkan Rudi Mantovani kebanyakan berupa lukisan
lanskap dan seni objek. Rudi sering menggunakan benda
temuan gitar listrik, seterika listrik, berbagai jenis
buah untuk menghasilkan seni objek yang diinginkan. Gitar
dan seterika dibuat seolah meleleh ke bawah, tangkai gitar
dibuat panjang hingga tiga meter, gitar dilengkungkan, dua
gitar masing-masing dilengkungkan dan disambung membentuk
huruf O. Rudi juga membuat gitar bertangkai sembilan dan
menyambung gitar akustik dengan gitar listrik dengan satu
tangkai. Objek ciptaan Rudi yang lain adalah membuat
tiruan berbagai macam buah seperti pisang, mentimun, apel,
dan semangka.
Pada karya Setelah Makan I (2006), Rudi membuat pisang
ukuran besar dalam kondisi setengah terkupas, dan bagian
yang terkupas dihias dengan motif batik parangrusak.35
Objek-objek buah
35 Mengapa Rudi Mantovani menghias buah pisang yang siapditelan itu dengan motif batik Jawa parangrusak? Apakah sekedarmain-main atau ada pesan yang tersembunyi?. Karya Rudi Mantovanibisa kita baca secara positif bahwa orang Minang misalnya atausuku lain setelah memahami budayanya sendiri (makanan utama)sebaiknya juga memahami budaya suku lainya seperti makan pisangAmbon rasa Jawa. Jika karya Rudi dibaca secara negatif, maka akandilihat bahwa dalam pandangan non-Jawa, orang Jawa itu sifatnyaparadoks, antara perkataan dan perbuatan tidak sama (antara kulityang bersih dan buahnya yang rumit) atau istilah kasarnyahipokrit.
Gambar 4: Rudi Mantofani, a. Setelah Makan 1.,2006, objek; b.Dessert, 2004, lukisan (Sumber: a. cp-foundation.org, b.artvalue.com)
yang lain seperti semangka, mentimun, dan apel ditampilkan
dalam kondisi dipotong melintang dan ada yang membujur.
Pada seni objek buah apel yang dibelah dua menjadi dua
bagian, penampang bagian yang tebal dan penampang bagian
yang tipis keduanya dilukis dengan objek pemandangan alam.
Hampir semua seni objek trimatra yang dihasilkan oleh Rudi
Mantovani kemudian dijadikan objek utama pada beberapa
lukisan lanskap. Seni objek berjudul : Setelah Makan I (2004-
2006), Lihat Isi (2004), dan Luas dan Terbatas 2 (2006) masing-
masing mejadi objek utama lukisan berjudul: Maka Jadi Besarlah
I (2005), Maka Jadi Besarlah 2 (2005), dan Luas dan Terbatas 1
(2005). Buah pisang dan buah mentimun atau labu dalam
lukisan-lukisan Rudi Mantovani mengalami pembesaran kedua
kalinya setelah dibesarkan menjadi seni objek trimatra
kemudian dibesarkan secara ilusif dalam lukisan.
Jumadi Alfi lahir di Lintau Sumatra Barat tahun 1973,
belajar melukis di Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
Karya-karya Alfi pada awalnya mirip dengan grafiti yang
banyak menonjolkan coretan huruf dan simbol secara
spontan. Sejak tahun 1998 hingga 2010 Alfi sudah
menyelenggarakan pameran tunggal sebanyak lebih dari
sepuluh kali di Yogyakarta, Jakarta, Singapura,
Kualalumpur, dan beberapa negara lain. Dari karya-karya
yang sudah dihasilkan Alfi dapat dikenali ciri-ciri
umumnya misalnya pembagian bidang sebagian dibagi dua
seperti lukisan pemandangan, sebagian lagi tanpa ada
pembagian dan pada beberapa karya dibagi menjadi banyak
bidang kecil. Warna cenderung monokrom ada yang terang
seperti abu-abu dan gelap seperti biru, hijau, coklat, dan
merah. Bentuk-bentuk representasi yang sering muncul dalam
lukisan Alfi adalah batu, tengkorak, dan tipografi yang
kebanyakan sengaja dibuat tidak terbaca kecuali pada
karya-karya pameran tunggal Life/Art # 101: Never Ending Lessons.
Bentuk-bentuk lain yang sempat ditampilkan Alfi pada
karya-karyanya cukup beragam ada binatang babi, tubuh
manusia, bagian tubuh manusia, arca Budha di atas teratai,
kaktus, benda-benda buatan dan lain sebagainya. Pada
sebagian karyanya lebih didominasi coretan-coretan atau
goresan yang tidak berbentuk. Karya-karya Alfi merupakan
kombinasi dari beberapa gaya ungkap seperti lanskap,
grafiti, kaligrafi, alam benda, dan lukisan abstrak.
Bentuk yang paling dominan dalam karya-karya Alfi
adalah tengkorak manusia dan batu dengan latar belakang
atau kadang-kadang latar depan tipografi atau tulisan yang
sulit dibaca. Tengkorak kepala manusia dilukis dari arah
depan, kadang-kadang dari samping kiri atau kanan dengan
cara pelukisan yang realis maupun gaya lain seperti
deformatif dan gambar linier atau sketsa. Objek batu
selalu dilukis secara realis (volumetrik) dengan ukuran
kecil lebih sering sebagai objek yang berdiri sendiri.
Pada beberapa karya Alfi, objek batu dikombinasikan dengan
berbagai objek lain seperti : tengkorak, tubuh dan bagian
tubuh manusia, kaktus, sketsa benda buatan manusia, bunga
teratai, arca Budha, dan sebagainya.
Penggambaran objek batu dan tengkorak manusia yang
dominan dalam karya lukisan Alfi maupun presentasi
kerangka manusia pada instalasinya, menimbulkan suatu
pertanyaan bagi para pengamat. Objek-objek yang sering
berulang dalam suatu karya seni rupa pastilah memiliki
makna khusus setidaknya bagi perupanya sendiri. Alfi
menganggap lukisannya sebagai rumah yang dapat berfungsi
sebagai terapi personal, sehingga ia perlu dua rumah untuk
merepresentasikan keinginan bawah sadarnya.36 Tengkorak
dan batu serta objek lainnya dalam karya Alfi pasti36 Wawancara Rustika Herlambang dengan Jumaldi Alfi,
Yogyakarta, 21 November 2009, dimuat dihttp://rustikaherlambang.wordpress.com/2009/11/21/jumaldi-alfi/keinginan, diakses 18 Februari 2011.
memiliki makna simbolis. Menurut Alfi di dalam masyarakat
tradisional Minangkabau keberadaan batu digunakan sebagai
tanda otoritas bagi kaum yang lebih tua atau sebagai tanda
batas wilayah. Alfi menggunakan tanda batu dalam karya-
karyanya sebagai penanda batas antara dunia imajiner dan
dunia nyata.37 Dalam tradisi Minangkabau terdapat suatu
ungkapan yang menggambarkan karakter masyarakatnya yaitu
marukuk ambiek batu yang artinya, merunduk mengambil batu
untuk kemudian dilemparkan kepada sesuatu yang mengancam.
Makna lebih luas dari ungkapan itu, jika orang Minang
tidak berhasil melawan kekerasan dari luar, mereka seakan
tunduk pada pelaku kekerasan tersebut sampai suatu saat
ketika sudah memiliki kekuatan penuh, akan menghantam
orang atau kelompok pelaku kekerasan.38
Tempat kelahiran Alfi di Lintau, kabupaten Tanah Datar,
Sumatera Barat adalah daerah bekas kerajaan Pagaruyung
yang didirikan oleh Adityawarman yang memiliki hubungan
37 Carla Bianpoen. “Alfi Jumaldi: The stone as signifier”,Surat kabar The Jakarta Post (3 Februari 2008), online,http://www.thejakartapost.com/ news/2008/03/02/alfi-jumaldi-the-stone-signifier.html diakses 18 Februari 2011.
38 Syamdani. 32.
darah dengan Majapahit. Di daerah bekas kerajaan
Pagaruyung itu terdapat banyak batu prasasti peninggalan
Adityawarman yang memeluk agama Budha Tantrayana.
Prasasti-prasasti itu ditemukan di beberapa tempat yang
jumlahnya kurang lebih sekitar dua puluh buah, ditulis
dengan huruf Palawa. Selain prasasti juga ditemukan arca
Amoghapasa dan Siwa Bhairawa yang ganas sebagai perwujudan
Adityawarman. Pada arca ini Siwa berdiri di atas mayat
korban dan lapik tengkorak manusia. Menurut Soekmono arca
Amoghapasa dikirim dari Singasari oleh Kertanegara dalam
ekspedisi Pamalayu antara tahun 1275-1292. Pada alas arca
Amoghapasa terdapat prasasti berangka tahun 1286 yang
menceritakan, atas perintah Kertanegara dikirimkan arca
Amoghapasa dengan 13 pengikutnya.39
Batu-batu yang tertata secara melingkar seperti tempat
musyawarah terdapat di dekat komplek prasasti Pagaruyung,
di situ terdapat situs Batu Batikam sebuah batu yang
berlubang kena tikam pedang seorang datuk. Tradisi
prasasti di Minangkabau hanya ada pada masa Adityawarman39 R. Soekmono. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2
(Yogyakarta:Kanisius, edisi ketiga, 1981), 64-65.
karena tidak ditemukan prasasti yang ditulis sebelum dan
sesudah masa kekuasaannya. Prasasti-prasasti Adityawarman
merupakan jejak Majapahit di tanah Melayu yang baru bisa
dibaca sebagian saja, yang sebagian lagi belum ada yang
bisa membaca, sehingga sejarah Minangkabau yang
berhubungan dengan Majapahit sebagian masih kabur.40
Dalam masyarakat Minangkabau terdapat dua kelompok
marga keturunan kerajaan Pagaruyung yaitu Koto Piliang dan
Bodi Caniago. Berdasarkan Tambo Alam Minangkabau yang
ditulis oleh Datuk Batuah Sango dinyatakan bahwa pembagian
dua keselarasan itu berdasarkan hasil mufakat antara nenek
Datuk Ketumanggungan dengan Datuk Perpatih Nan Sabatang
dan Datuk Suri Dirajo. Pemerintahan Datuk Ketumanggungan
bernama Koto Piliang berasal dari kota pilihan, atau dari
kata yang tidak boleh dipalingkan. Pemerintahan Datuk Perpatih
40 Tradisi tulis (prasasti) dan tradisi visual (arca dancandi) di Minangkabau pada masa pra Islam hanya terjadi di zamanAdityawarman yang secara genealogis dan politis berhubungandengan Majapahit. Tambo-tambo Minangkabau yang ditulis pascaAdityawarman tidak banyak menyebut peran Adityawarman karena iaseorang ‘sumando’. Sumando dalam adat Minangkabau adalah laki-laki yang tidak memiliki hak waris dan otoritas kultural karenaberdasar tradisi matriliniat otoritas kultural hanya diberikankepada ninik mamak atau seorang paman dari keluarga ibu yangbergelar penghulu.
Nan Sabatang bernama Bodi Caniago yang berasal dari budi
yang berharga.41
Suasana alam Minangkabau khususnya di daerah bekas
kerajaan Pagaruyung di mana terdapat banyak batu prasasti
dan situs batu lainnya sangat membekas dalam pikiran Alfi.
Ketika sekolah di Yogyakarta ia semakin ingin tahu sejarah
daerah asalnya yang menurut orang Minang dirasakan tragis.
Tambo tentang sejarah Minangkabau yang sering diceritakan
oleh para orangtua kepada anak-anak di daerah asal Alfi
ikut memperkaya masalalunya. Dalam sejarah Indonesia telah
terjadi beberapa kali kontak fisik sebagai bentuk
perlawanan penguasa Minang terhadap pusat kekuasaan yang
berada di Jawa sejak zaman Singasari, Majapahit, hingga
pemerintah Republik Indonesia pada zaman Soekarno.
Ekspedisi Pamalayu ke Sumatera yang dilakukan atas
perintah Kertanegara dari Singosari pada tahun 1275-1292
tidak terdapat keterangan tentang banyaknya korban.
Setelah Adityawarman turun tahta pada tahun 1376,
41 Is Sikumbang. “Alam Minangkabau”, online, http://palantaminang. wordpress.com/sejarah-alam-minangkabau/b-alam-minangkabau/ diakses 19 Februari 2011.
penerusnya memutuskan untuk memisahkan diri dari
Majapahit. Pada tahun 1377 Hajam Wuruk berhasil menumpas
pemberontakan Pagaruyung. Dalam legenda-legenda
Minangkabau diceriterakan pertempuran dahsyat dengan
tentara Jawa di daerah Padang Sibusuk. Daerah bekas tempat
kejadian itu dinamakan demikian karena di tempat itu
dahulu banyak terdapat mayat yang bergelimpangan.42
Peristiwa yang paling mutakhir adalah pemberontakan
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang
digagalkan oleh tentara Soekarno pada tahun 1958.
Pemberontakan yang melibatkan Central Intelligence Agency
(CIA) ini telah memakan korban ribuan tentara dari kedua
belah pihak dan para pendukung PRRI.43
Jumaldi Alfi Caniago sebagai keturunan marga Bodi
Caniago tentu memiliki hubungan emosional dengan sejarah
Minangkabau. Ia merasa gelisah memikirkan perjalanan hidup
42 Ensiklopedia Wapedia, “Adityawarman”,online, tersedia dihttp://wapedia.mobi/id/Adityawarman, diakses 19 Februari 2011.
43 Merle Calvin Ricklefs. Sejarah Indonesia modern 1200-2004(Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), 520, terjemahan daribuku A History of Modern Indonesia since 1200, Third Edition (Palgrave,2001), 312-422. Setelah peristiwa pemberontakan PRRI, dua partaiIslam yaitu Masjumi pimpinan Natsir dan PSI pimpinan Sjahrir(keduanya orang Minang) dibubarkan oleh Soekarno.
etnis Minang yang ia ketahui dari berbagai sumber seperti
mitos, legenda, tambo maupun cerita-cerita dari para
orangtua. Sumber-sumber sejarah yang ditulis oleh para
penulis di luar orang Minang memperkaya pemahaman Alfi
tentang daerah asalnya. Dalam kasus PRRI misalnya banyak
terjadi perbedaan pandangan dalam melihat kasus itu, para
penulis banyak melihat kasus ini sebagai pemberontakan,
tetapi para pelaku dan penulis etnis Minang menganggap
bukan pemberontakan.44
Alfi dan teman-temannya di Kelompok Jendela sudah
diingatkan oleh para orangtua mereka agar tidak mengikuti
aktivitas politik ketika belajar di Yogyakarta, namun
dianjurkan untuk mempelajari sejarah daerah asalnya. Para44 Penulis sejarah dari Barat menganggap PRRI sebagai
pemberontakan, lihat, Audrey R. Kahin. Dari pemberontakan ke integrasi:Sumatra Barat dan politik Indonesia, 1926-1998 (Jakarta: Yayasan OborIndonesia, 2005), 282-327, dari judul asli, Audrey R. Kahin.Rebellion to Integration, West Sumatra and the Indonesian Polity 1926-1998. Penulislain seperti Syamdani tidak melihat kasus PRRI sebagaipemberontakan ia justru menganggap peristiwa itu sebagai reaksidari etnis Minang yang memiliki karakter tidak mau ditekan.Lihat, Syamdani. PRRI, Pemberontak atau Bukan? (Yogyakarta: MediaPressindo, 2008), 14-33. Ventje Samual, seorang pelakupemberontakan Permesta yang bersama PRRI melawan pemerintah pusatmenganggap Permesta bukan pemberontakan, tetapi ia mengakuisebagai memberontak terhadap kezaliman, ia juga mengaku dibantuAmerika. Lihat, Herman Nicolas Ventje Sumual: "Permesta BukanPemberontakan", Majalah Tempo, (06 Desember 1999).
perupa Kelompok jendela memenuhi harapan para orangtua
mereka, kemudian memfokuskan diri pada ekspresi individu
masing-masing anggotanya. Mereka sepakat untuk menolak
politik dan memilih seni rupa dengan memperkuat karya
mereka pada saat para perupa di Yogyakarta sedang
menyuarakan kritik sosial pasca reformasi tahun 1998.
Seorang penulis dan kurator dari Malaysia, Karim Raslan
memandang komitmen para perupa Kelompok Jendela itu nampak
subversive dan merupakan sebuah tindakan politik tingkat
tinggi.45
Alfi yang telah banyak membaca buku tentang sejarah
Minangkabau semakin mengetahui fakta sejarah yang
berhubungan dengan daerah itu. Ia berusaha mengakui
kembali budayanya, merayakannya, dan mengatasi melalui
pilihan profesinya sebagai perupa. Pada saat masyarakat
Minang berusaha memulihkan trauma terhadap ’Perang melawan
Jawa’, Alfi menunjukkan sensibilitas seninya tidak
45 Karim Raslan. “Looking for sanity amidst chaos”, Suratkabar tabloid The Star, Minggu (5 April 2009),online,http://thestar.com.my/lifestyle/story.asp?file=/2009/4/5/lifearts/3530459&sec=lifearts,diakses 20 Februari.
terpisah dengan biografi pribadinya.46 Karya-karya Alfi
merupakan refleksi dari fase dalam hidupnya seperti
terlihat pada seri Meditation, Poscards for the Past dan Signs dapat
dipahami sebagai aliran dari evolusi pribadinya, dalam
arti tertentu merupakan sebuah perjalanan mencari fakta
dan penyembuhan.47
Pada karya seri Reborn (2002), Poscard 003, 008, 009,
010 (2005), dan Meditasi 014(2005), Alfi menampilkan
berbagai ikon arca Budha dengan sikap amitaba dan wairocana,
kepala Budha, torso,
46 Karim Raslan. “Jumaldi Alfi: Life/Art #101: Never EndingLesson”, esei pada katalog pameran tungal Alfi di ValentineWillie Fine Art (VWFA) 21 – 28 Okt. 2010 di Kualalumpur. Lihathttp://www.vwfa.net/kl/offsiteDetail. php?oid=60 diakses 20Februari 2011.
47 Carla Bianpoen. “Alfi Jumaldi unfolds latest oeuvre inSingapore”, Surat kabar Jakart Post, http://www . Indonesian contemporary.com /Images /Press/ 159081214 Alfi_unfoldlatestoeuvre .pdf diakses 20 Februari 2011.
Gambar 5 : Jumaldi Alfi, a. Reborn, 2002; b. Postcard #009The 2nd Notes, 2005 (Sumber: a. 33ayction.com; b. mutualart.com)
teratai, kaktus, batu, dan benda-benda lainnya. Ikon-ikon
Budha dalam beberapa karya Alfi dapat dimaknai sebagai
suatu laku meditasi, sedangkan teratai sebagai lapik
memiliki makna kebijakan dan kecerdasan. Pendiri kerajaan
Pagaruyung adalah Adytyawarman seorang pemeluk Budha
Tantrayana.48 Bagi masyarakat Minangkabau yang menganut
kekerabatan matriliniat tidak begitu menganggap penting peran
Adityawarman karena ia hanyalah seorang sumando.49 Terdapat
satu karya Alfi yang memperkuat obsesinya tentang posisi
Adityawarman dalam sejarah Minangkabau yaitu karya
berjudul Datang dari Timur (2004). Karya ini terdiri dari 9
panel, di bagian tengah terdapat pemandangan dengan
latarbelakang gunung dan latardepan hamparan tanah kosong
yang di atasnya terdapat sebuah konstruksi rumah dalam
bentuk sketsa dan dikelilingi lima buah batu. Pada bagian
kiri atas terdapat siluet laki-laki berkepala gundul,
sementara di bagian bawahnya dilukiskan bunga teratai
48 Arca perwujudan Adityawarman ditemukan di Padang Roco,Sawahlunto, Sumatera Barat setinggi 3 meter merupakan arca Siwasebagai Bhairawa yang berdiri di atas mayat bayi dengan lapiktengkorak manusia. Tangan kiri memegang mangkuk darah dan tangankanan memegang belati.
49 Monaris Simangunsong dkk.. ”Kisah Telur di Batu Basurek”,Majalah Tempo online (14 November 1987). Orang sumando adalahlaki-laki atau menantu di keluarga istri dalam masyarakatMinangkabau yang tidak memiliki hak waris. Pada tahun 1950-anawal Menteri Pendidikan Mohamad Yamin hendak mendirikanUniversitas Adityawarman di Sumatera Barat,tetapi masyarakat disana menolaknya, sehingga pada tahun 1956 diganti menjadiUniversitas Andalas. Lihat, Kahin, 1-14. Fakta ini menunjukkanbahwa identitas etnis Minang secara sengaja dikaburkan darihubungannya dengan Majapahit.
merah. Alfi melukiskan laki-laki berkepala gundul pada
bagian kanan atas, sedangkan di bawahnya dilukiskan
pemandangan dengan warna biru gelap dengan objek utama
tangga di bagian kanan bawah. Laki-laki di atas teratai
identik dengan sang Budha, yang dalam konteks ini di mata
Barat dapat dianggap tokoh dari Timur. Dalam konteks
hubungan Minang dan Jawa maka arah timur berarti Majapahit
atau Jawa tempat Adityawarman tokoh pendiri Kerajaan
Pagaruyung berasal. Pemandangan di tengah merupakan alam
Minangkabau yang dilengkapi dengan konstruksi sejarah dan
budayanya, sedangkan batu-batu itu adalah prasasti dan
fakta historis peninggalan Adityawarman. Batu-batu kecil
itu juga bisa dibaca sebagai pengaruh budaya Jawa yang
dibawa Adityawarman tetapi ditempatkan di luar alam bawah
sadar masyarakat Minang.
Karya-karya Alfi yang lain banyak berhubungan dengan
masa lalunya atau masalalu orang Minang. Judul-judul yang
dipilih Alfi untuk karya semacam itu misalnya: Monument
Series (2006), Memoration Series (2006), Living in the Past (2006),
Seri Ingatan (2006), Build Back (2008), Monument Serie Memory
(2008), Melting Past (2009), dan Melting Memories (2011). Pada
beberapa seri karya tersebut Alfi tetap menampilkan ikon-
ikon tengkorak, batu, dan kaktus. Penanda yang paling
banyak muncul dalam karyanya adalah batu kecil yang lebih
sering diletakkan di bagian tepi dari bidang kanvas.
Menurut pengakuan Alfi, penanda batu dalam karya-karyanya
terinspirasi oleh mitos klasik Yunani yang ditulis oleh
Albert Camus yaitu Sisyphus.50 Mitos ini menceritakan
Sisyphus seorang raja dari Korintus karena
ketidakacuhannya terhadap para dewa ia dikutuk dan dihukum
dengan pekerjaan mendorong batu menuju ke puncak bukit
agar sampai di puncak menggelinding lagi ke bawah.
Pekerjaan yang harus diulang ini merupakan pekerjaan yang
tidak berguna dan tidak menghasilkan apa-apa. Camus
menganggap Sisyphus adalah pahlawan absurd. Dia mencintai
hidup dan membenci kematian. Perasaan absurd ini muncul
sebagai fungsi dari tubrukan antara dunia dan keinginan
yang kita buat sebagai makhluk rasional. Secara spesifik,
absurditas muncul dari konfrontasi antara “kebutuhan50 Jumaldi Alfi. dalam, “Through Jasmine’s Eyes”, Majalah
Indonesia Tatler, (September 2008) , 186.
manusia dan keheningan dunia yang tak rasional”51 Camus
menganggap bahwa absurditas harus mendorong pemberontakan
demi keadilan dan solidaritas manusia. ‘I Rebel therefore
we exist’.52
Sejak awal tahun 2000-an, Alfi dengan tekun telah
’menggelindingkan’ batu-batu kecil ke kanvas-kanvasnya
secara berulang-ulang tanpa merasa bosan. Batu-batu kecil
itu selalu dilukiskan secara realis menandakan bahwa beban
sejarah masalalu itu benar-benar nyata dalam hidupnya.
Tengkorak-tengkorak dalam karyanya juga sering dilukis
secara realis sebagai tanda bahwa korban-korban dalam
sejarah daerah Minang pada pemberontakan Pagaruyung (tahun
1377) dan PRRI (tahun 1958) itu juga nyata. Tulisan-
tulisan dan corat-coret yang tak terbaca dalam kanvas-
kanvas Alfi menggambarkan kekaburan sejarah Minangkabau
yang tidak dialami secara langsung oleh Alfi. Kekaburan
sejarah disebabkan oleh beberapa hal misalnya keengganan
para ahli untuk membaca prasasti Adityawarman yang belum
51 Albert Camus. The Myth of Sisyphus & Other Essays, terjemahanJustin O’Brien (New York: Vintage Books, 1955) , 21.
52 Albert Camus. The Rebel , terjemahan Anthony Bower (NewYork, Vintage Books, 1956) , 22.
sempat diterjemahkan. Tambo dan mitos yang berkembang di
masyarakat Minang sering bersifat subjektif.53
Terdapat beberapa karya Alfi lainnya yang menarik
untuk diamati yaitu karya-karya yang menampilkan tanda
atau ikon tanaman kaktus. Pemunculan tanda kaktus pada
beberapa karya Alfi biasanya tidak berdiri sendiri, tetapi
tanda ini muncul bersama tanda lainnya seperti batu,
tengkorak, teks, manusia, dan tanda lainnya. Karya-karya
Alfi yang menampilkan tanda kaktus adalah: Silent but not Alone
(2008), I Believe a Miracle (2008, 2009), I Believe a Miracle (There was a
Good), (2009), Renewal Series 1-E (2009), I am Legend #1 dan #6
(2009), Born on July (2009), Fur Elise (2009), Night Walker (2009-
2010), dan Fort of Mind (2011).
53 Mitos tentang asal-usul suku Minangkabau yangmenceritakan tentang kerbau betina Minang menang setelah beradudengan kerbau jantan Jawa. Sebenarnya mitos ini bisa dibacasecara bebas yaitu bahwa budaya matriliniat Minang telahmemenangkan atau berhasil meniadakan hubungan darah dengankerajaan Majapahit karena kerajaan Jawa ini menganut budayapatriliniat. Mitos tentang tempat di Sumatera Barat yang bernamaPadang Sibusuk yang dipercaya sebagai tempat penguburan korbanpemberontakan Pagaruyung digambarkan seperti ‘Killing Field’korban pembantaian oleh tentara Kmer Merah. Persepsi yangberkembang di masyarakat Minang terhadap pemberontakan PRRIberbeda dengan persepsi masyarakat Indonesia pada umumnya. OrangMinang merasa tidak memberontak, mereka hanya ingin menuntutkeadilan dan menolak komunisme.
Kaktus adalah sejenis tanaman yang dapat tumbuh di
gurun-gurun tandus dan di tanah yang gersang. Tanaman ini
dapat menyimpan air sehingga mampu bertahan pada musim
kemarau. Kebanyakan jenis tanaman kaktus memiliki duri
yang tajam, tetapi pada saat tertentu menghasilkan bunga
yang indah. Tanda kaktus dalam karya-karya Alfi dapat
dibaca sebagai simbol kekuatan, ketabahan, dan kemampuan
bertahan hidup dalam menghadapi pluralitas budaya
sekaligus pluralitas seni. Persoalan hidup yang
dihadapinya semakin kompleks sehingga sebagai perupa asal
Minang yang menjalankan tugas kultural ‘merantau’, Alfi
dan kawan-kawan harus mampu bertahan di tengah dunia yang
semakin kompetitif.
Karya-karya Alfi yang juga menarik untuk diamati adalah
sejumlah karya yang bertema pujian atau penghormatan
terhadap tokoh tertentu terutama para perupa dari Barat
seperti misalnya Joseph Beuys, Martin Kippenbarger, Karel
Appel dan lain-lain. Beberapa karya Alfi yang menyanjung
tokoh tertentu adalah : Doa to Karel Appel (1995), Ode to Sisyphus
(2006), Ode to my Father (2006), Homage to Martin Kippenbarger
(2007), A Letter to Joseph Beuys (2008), Homage to Joseph Beuys
(2008), Fort of Soul, Fort of Mind, Homage to Baselitz (2008), dan
lain-lain. Pada pameran tunggal Jumaldi Alfi Life/Art #101: Never
Ending Lesson (2010), Alfi menyajikan karya seri blackboard,
yaitu sejumlah lukisan yang meniru papan tulis dan tulisan
dari kapur. Teks pada lukisan papan tulis itu sebagian
diambil dari pernyataan konseptual Josep Beuys dan tokoh
lainnya. Pernyataan para tokoh itu tidak ditulis apa
adanya oleh Alfi tetapi diparodikan sehingga maknanya
berubah.
Tanda akan munculnya karya-karya lukisan Alfi seri
blackboard sebenarnya dapat dilacak sejak tahun 2005 pada
karya Poscard 005 The Blackboard (2005), Colour Guide Series 'Hommage
To Beuys'(2007) dan A Letter to Joseph Beuys (2008). Pada karya
Homage to Beuys, Alfi sudah menampakkan simpati dan
penghormatan kepada Joseph Beuys dengan melukis papan
tulis dengan teks ‘I Knew the Moment Can Arrived to
Killing the Past’. Joseph Beuys adalah perupa Jerman pada
tahun 1970-an mengadakan kuliah-performance di beberapa kota
di Eropa dan Amerika dengan menggunakan elemen utama
gambar papan-tulis (blackboard drawing). Gambar papan-tulis
Beuys diinspirasi oleh gambar-gambar papan-tulis Rudolf
Steiner seorang penemu antroposofi dari Jerman yang pada
tahun 1920-an mengadakan kuliah umum di beberapa kota di
Eropa dengan menggunakan gambar papan-tulis. Gambar papan-
tulis Steiner merupakan bagian esensial dari proses
pengetahuan, sebuah proses di mana hal itu selalu
merupakan persoalan manifestasi spirit yang benar-benar
menggembirakan sebelum membayangkan, mengingat, dan
menghubungkan secara benar ke yang satu dengan lainnya.54
Melihat lebih dekat pada realitas proses kematian
pada peradaban dan melakukan latihan mengamati proses
kematian di alam seperti dideskripsikan dalam buku
Steiner, Knowledge of the Higher Worlds, How is it Achieved? , Beuys
menyatakan hal itu sebagai persyaratan untuk kebangkitan
spiritual manusia. Beuys mempercayai hal itu sebagai
54 Walter Kugler. ”Cosmic Poetry, Rudolf Steiner’sBlackboard Drawings” dalam Rudolf Steiner & Walter Kugler.Blackboard Drawing 1919-1924 (Forest Row, East Sussex: Rudolf SteinerPress, 2003) , 7-16.
sebuah dunia baru yang berkembang. Dunia baru itu adalah
’seni-patung kehangatan’ atau ’seni-patung sosial’.55
Papantulis adalah lambang dari otoritas kegurubesaran
dalam sistem Jerman di mana Beuys menjadi guru besar seni
rupa dan sebagai perupa. Simbol-simbol sains, terminologi
saintifik, dan tangan orang dewasa yang percaya diri,
semuanya menyatakan bahwa si penulis adalah orang
berpendidikan. Citra papantulis pada lukisan Twombly
menunjukkan kutub yang berbeda karena hanya berhubungan
dengan pengalaman biasa bukan suatu pengalaman dari
seseorang yang memiliki otoritas.56
Gambar papantulis Steiner dan Beuys memang bukan
lukisan seperti lukisan Alfi seri blackboard atau lukisan
citra papantulis Twombly. Gambar papantulis Steiner adalah
unsur penting dalam kuliah umumnya sebagai ahli
antroposofi, sedangkan gambar papantulis Beuys merupakan
unsur penting dalam performance dialogisnya. Lukisan
55 Joseph Beuys & Volker Harlan. What is Art? Conversation with JosephBeuys (Forest Row: Clairview Books, 2007) , 107-108.
56 Arthur C. Danto. The Madonna of the Future: Essays in a Pluralistic Artworld (Berkeley dan Los Angeles: University of California Press,2000) , 88-89.
papantulis Alfi dan Twombly dengan sengaja meniru citra
papantulis ke permukaan kanvas, kedua perupa ini tidak
menggunakan media lukisan mereka sebagai bagian dari
kuliah umum atau performance. Beuys lebih mengutamakan
proses atau aksi-aksi dalam performance, kuliah, atau
monolognya dibandingkan dengan artefak atau bentuk fisik
karyanya yang disimpan di museum. Sikap Beuys dalam
berkesenian merupakan bentuk perlawanan terhadap
konsumerisme. Beuys lebih tertarik dengan persoalan
kemanusiaan seperti yang ia kagumi dari pemikiran Rudolf
Steiner. Kuliah Steiner About Bees tahun 1923 melengkapi
titik awal keistimewaan estetika Beuys. Steiner melihat
koloni lebah sebagai model bagi perkembangan manusia.57
Gambar papan-tulis Beuys masih menimbulkan masalah
apakah itu bisa dikategorikan sebagai karya seni rupa atau
hanyalah gambar biasa di permukaan papan-tulis. Lukisan-
lukisan papan-tulis Alfi jelas merupakan karya seni rupa
yang memiliki nilai ekonomi sebagaimana karya Alfi yang
lain. Alfi juga menyamakan kondisi psikologis masyarakat57 David Hopkins. After Modern Art 1945-2000 (Oxford, New York:
Oxford University Press, 2000) , 88.
Minangkabau yang trauma terhadap peristiwa penumpasan
’pemberontakan PRRI’ dengan kondisi masyarakat Jerman
pasca Perang Dunia II. Keyakinan Beuys terhadap seni yang
dapat menyembuhkan luka masyarakat memberi inspirasi Alfi
untuk menjadikan karya-karyanya sebagai media untuk
menyembuhkan luka atau trauma pribadi meskipun dia sendiri
tidak mengalami. Beuys menjadikan biografinya sendiri
sebagai sekuen dari karya-karyanya dan menjadikan semua
realitas historis hilang di balik mitos pahlawan perupa
yang diciptakan sendiri.58
Alfi yang lahir tahun 1973 dan hanya beberapa tahun
tinggal di kampung halamannya, ia memiliki imajinasi yang
tinggi terhadap peristiwa ’pemberontakan PRRI’ tahun 1958.
Kisah hidupnya yang pribadi ditambah dengan trauma
masyarakat pasca peristiwa itu menjadi ramuan yang pas
untuk ’mengestetiskan’ peristiwa politik. Art world
internasional kini sepertinya tidak lagi membutuhkan karya
seni kreasi perupa Asia yang menampilkan budaya eksotik
sebagai tanda keliyanan. Tanda keliyanan dari seni rupa58 Stefan Germer. ”Haacke, Broodthaers, Beuys”, majalah
October, Vol. 45 (Summer, 1988), 63-75.
Asia ataupun Afrika adalah sikap kritis perupa terhadap
pemerintah dari negara asal mereka.59 Karya-karya Alfi
selalu dikaitkan dengan masalalu masyarakat Minangkabau
yang mengalami trauma sejarah yang didramatisir seakan-
akan merupakan ’perang melawan Jawa’ dan banyak menelan
korban di pihak masyarakat di Sumatera Barat.60
59 Rasheed Araeen. “A New Beginning: Beyond PostcolonialCultural Theory and Identity Politic”, dalam, Rasheed Araeen danSean Cubitt, ed, The Third Text Reader on Art, Culture and Theory (London,2002) , 333-346.
60 Lihat esei Karim Raslan, “Jumaldi Alfi: Life/Art #101:Never Ending Lesson”, online, http://www.vwfa.net, diakses 6 Maret2011.
Gambar 6: Jumaldi Alfi, a. Life/Art #101: Never Ending Lesson, 2010,instalasi; b. How to Explain, 2010, lukisan
(Sumber: a. sangkringartspace.net, b. artinasia.com)
Salah satu karya Alfi pada seri blackboard yang masih
mempresentasikan simbol visual tengkorak manusia adalah
karya berjudul How to Explain. Karya Alfi ini diapropriasi
dari karya performance Beuys yang berjudul How to Explain
Pictures to Dead Hare tahun 1965. Pada karya Alfi digambarkan
sketsa tengkorak dengan garis skala, di samping sketsa
tengkorak digambarkan bagan grafik yang menunjukkan jumlah
sesuatu. Melalui karya ini Alfi ingin menjelaskan kepada
penonton tentang jumlah korban dalam peristiwa berdarah
di kampung halamannya.
Perupa anggota Kelompok Jendela yang lain adalah
Yunizar dan Yusra Martunus. Yunizar yang berlatar belakang
pendidikan seni lukis banyak menghasilkan karya lukisan
dengan gaya mirip Alfi dan beberapa karyanya menunjukkan
ciri seperti gambar anak-anak. Yusra Martunus dengan
keahlian seni patung banyak menghasilkan seni objek.
Sebagian karya seni objek yang dihasilkannya telah
diwujudkan dalam bentuk seni lukis. Pemindahan seni objek
tiga dimensional ke permukaan kanvas merupakan fenomena
baru yang dipelopori oleh perupa Kelompok Jendela.
Karya-karya perupa Kelompok Jendela yang fenomenal itu
jika diamati lebih jauh maka masih berkait dengan akar
budaya mereka yaitu Minang yang menjunjung tinggi adat dan
budaya tradisi yang bersumber pada kearifan lokal.
Filsafat yang berbunyi ‘Alam terkembang jadi guru’
merupakan sumber rujukan bagi masyarakat Minang termasuk
para perupa kelompok Jendela. Karya-karya Handiwirman
banyak mengeksploitasi benda-benda remeh yang kemudian
dibesarkan dalam bentuk seni objek dan lukisan alam benda.
Karya-karya Rudi Mantovani juga menonjolkan benda-benda
alam seperti buah-buahan yang dibesarkan dan pembesaran ,
pemanjangan, pembengkokan benda-benda temuan seperti
guitar dalam bentuk sei objek tiga dimensi. Rudi Mantovani
banyak menghasilkan karya seni lukis pemandangan yang
tidak berkait dengan keindahan alam Minangkabau. Karya-
karya Rudi Mantovani lebih mengutamakan segi keanehannya
dan parodinya dibandingkan dengan kelaziman sebuah karya
pemandangan.
Karya-karya Jumaldi Alfi lebih banyak berupa seni lukis
dan sedikit instalasi dengan banyak menampilkan simbol-
simbol dari alam dan kehidupan manusia. Alfi lebih peduli
terhadap sejarah budaya dan politik Minang yang jarana
disentuh oleh perupa lainnya. Bagi Alfi karya seni dapat
digunakan sebagai terapi penyembuhan terhadap luka-luka
sejarah suku bangsa Minang dalam sejarah Indonesia. Secara
visual karya-karya lukisan Alfi merupakan gabungan dari
grafiti, lukisan pemandangan, dan alam benda. Benda-benda
alam yang sering tampil dalam karya Alfi misalnya batu,
kaktus, dan teratai. Alfi juga sering menampilkan bentuk
binatang dan manusia (tengkorak, torso, dan tubuh utuh),
serta benda buatan manusia seperti patung Budha, rumah.
Salah satu ciri penting dari karya Alfi hádala
ditampilkannya teks yang Madang terbaca dan Madang tidak
terbaca.
Karya-karya para perupa Kelompok Jendela secara umum
masih bersumber dari tanah asal, alam atau ranah Minang
yang mereka tinggalkan. Alam Minangkabau dengan adat yang
ketat tetap menjadi landasan berkarya, sedangkan secara
visual disesuaikan dengan konteks ‘rantau’. Para perupa
Kelompok Jendela mengkombinasikan “root” atau akar budaya
Minang. Dengan “route” atau gerak dinamik dari kehidupan
rantau. Alam dan rantau, atau “root” dan “route” merupakan
kombinasi dari masa lalu dan masa kini yang harmonis.
V. Kesimpulan
Berdasarkan kajian terhadap masalah politik identitas
pada karya perupa Kelompok Jendela maka dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Politik identitas yang diungkapkan para perupa diaspora
Minang (Kelompok Jendela) sebagai sesuatu yang
primordial, sebagai strategi dalam menghadapi persaingan
dalam art world di Yogyakarta dan internasional. Melalui
politik identitas para perupa Kelompok Jendela dan
perupa Minang lainnya dapat membedakan diri mereka
dengan yang lain. Politik identitas sekaligus juga
sebagai cara untuk merebut pasar yang selama ini
dikuasai oleh seni rupa gaya tertentu.
2. Kelompok Jendela dan perupa Minang di Yogyakarta telah
ikut andil dalam memperkaya pluralisme seni rupa
kontemporer di Yogyakarta. Reputasi mereka yang
fenomenal telah merangsang perupa dari komunitas lainnya
untuk terus kreatif sehingga semakin memperkuat art wolrd
Yogyakarta di forum internasional.
3. Politik identitas dalam karya-karya perupa Kelompok
Jendela secara visual dan wacana memiliki keberagaman.
Secara umum karya-karya mereka masih bersumber dari
budaya dan alam Minangkabau. Strategi visual yang
dilakukan sengaja menghindari seni rupa yang berbau
politik, namun demikian dengan sindiran yang lebih halus
karya mereka menyiratkan kritikan yang cukup tajam.
Daftar Pustaka :
Agus Burhan, “Kelahiran dan Perkembangan Gerakan Seni RupaBaru Indonesia“, Jurnal Panggung Vol. 20, No. 1, Januari-Maret 2010.
Alia Swastika. ”Melampaui Estetika Darurat”,dalamhttp://aliaswastika.multiply.com/reviews/item/111,diakses 4 Februari 2011
Bhabha, Homi K, The Location of Culture (New York: Routledge,2005).
Bianpoen Carla. “Alfi Jumaldi: The stone as signifier”,Surat kabar The Jakarta Post (3 Februari 2008),
Camus Albert. The Myth of Sisyphus & Other Essays, terjemahan JustinO’Brien (New York: Vintage Books, 1955)
Cohen, R. . Global diasporas: An introduction. (London: UCL Press,1997). Danto Arthur C.. The Madonna of the Future: Essays in a Pluralistic Art world (Berkeley dan Los Angeles: University of CaliforniaPress, 2000)
Djuli Djatiprambudi , “Representasi Identitas di MedanPasar Seni Lukis Indonesia”, ITB Jurnal. Visual Art.Vol. 1 D, No. 1, 2007.
--------------, ”Komodifikasi Seni Rupa KontemporerIndonesia”, Jurnal Panggung Vol. 20, No. 1, Januari-Maret 2010.
FindArticles.com. 31 Jan, 2009. (online) http://findarticles.com /p/ articles/mi_m1248/is_n5_v81/ai_13701438, diakses 28 Maret 2011.
Giddens, Anthony, Masyarakat Post-Tradisional,(Yogyakarta:IRCiCoD,
2003) terjemahan Ali Nur Zaman, buku asli, Living in Post-Traditional
Society, (Cambridge: Polity Press, 1994).
Hall, Stuart, “The Spectacle of ‘Other’”, dalam Hall,Stuart, Representation : Cultural Representation and Signifying Practice (London: Sage, 2003).
-------------- , “Cultural Identity and Diaspora”, dalam,Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth; dan Tiffin, Helen, The Post-ColonialStudies Readers, edisi ke-2 (New York: Routledge, 2006). Maret 2011.
---------------, “Cultural Identity and Diaspora” dalam J.Rutherford , ed, Identity:Community, Culture, Difference (London:Lawrence and Wishart, 1990).
Heartney, Eleanor, "Identity politics at the Whitney -multiculturalism explored in Whitney Museum of Modern Art's 1993Biennial art exhibition" Art in America.
Hopkins David. After Modern Art 1945-2000 (Oxford, New York:Oxford University Press, 2000)
Iris Marion, Young Justice and the Politics of Difference (Princeton: Princeton University Press, 1990).
Kahin. Audrey R., Dari pemberontakan ke integrasi: Sumatra Barat dan politik Indonesia, 1926-1998. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).Karim Raslan. “Looking for sanity amidst chaos”, Surat kabartabloid The Star, Minggu (5 April 2009)
Kato, Tsuyoshi, Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif
Walter Kugler. ”Cosmic Poetry, Rudolf Steiner’s BlackboardDrawings” dalam Rudolf Steiner & Walter Kugler. Blackboard Drawing1919- 1924 (Forest Row, East Sussex: Rudolf Steiner Press, 2003) Sejarah, (Jakarta: Balai Pusaka,2005.
Lombard Denys. Nusa Jawa Silang Budaya: Batas-batas Pembaratan(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005)
Ricklefs, Merle Calvin. Sejarah Indonesia modern 1200-2004(Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007)
R. Soekmono. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2 (Yogyakarta:Kanisius, edisi ketiga, 1981)
Said, Edward, Orientalism, (New York; Vintage Books, 1978).
Syamdani, PRRI, Pemberontak atau Bukan?, (Yogyakarta:MediaPresindo, 2008).
Tololyan, Khachig, “Armenian Diaspora”, dalam MelvinEmber,Carol R. Ember,Ian Skoggard, ed, Encyclopedia of Diasporas: Immigrantand Refugee Cultures Around the World, (New York: Springer Science+Business Media Inc., 2005).
Wikipidia, Ensiklopedia Bebas, http://en.wikipedia.org/wiki/Identity_ politics, diakses 17 Februari 2009.
Zulfikri Suleman dan Kurniawan Junaedhie. ed, Demokrasi untuk Indonesia: pemikiran politik Bung Hatta (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010)