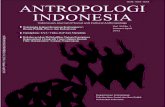REPRESENTASI IDENTITAS KULTURAL DALAM LAGU ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of REPRESENTASI IDENTITAS KULTURAL DALAM LAGU ...
32
Prolitera, 1(1): Juli 2018, ISSN 26216795
PROLITERA
Jurnal Penelitian Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
STKIP Santu Paulus Ruteng, e-mail: [email protected]
Available online: http://jurnal.stkipsantupaulus.ac.id/index.php/jpro/
REPRESENTASI IDENTITAS KULTURAL
DALAM LAGU-LAGU POP MANGGARAI
Ans. Prawati Yuliantari, Siprianus Sion, Hilaria Serlina Galung,
Maria Trifina Endang, Oktavianus Agung
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
STKIP Santu Paulus Ruteng
E-mail: [email protected]
Abstrak
Salah satu cara orang Manggarai untuk melukiskan dinamika yang terjadi dalam kehidupan sosial, politik, dan
budayanya adalah melalui lagu tradisional yang berakar dari tradisi tutur (oral tradition). Hal itu berkaitan
dengan fungsi lagu dalam masyarakat Manggarai sebagai sarana untuk meneruskan nilai-nilai dari para orang
tua kepada anak-anaknya. Selain berfungsi sebagai alat penerus tradisi dan sarana untuk mengekspresikan
dinamika masyarakat, lagu-lagu itu juga menampilkan identitas kultural orang Manggarai. Representasi
identitas berupa kebiasaan, adat istiadat, nilai-nilai, dan norma-norma itu ditampilkan dalam lirik lagu pop
daerah Manggarai. Berdasarkan fenomena itu maka terdapat dua pertanyaan penelitian, yaitu: apa bentuk-
bentuk identitas kultural yang diperlihatkan dalam musik pop Manggarai dan bagaimana identitas kultural itu
ditampilkan dalam lirik lagu-lagu pop Manggarai. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dipergunakan
metode discourse analysis guna mengidentifikasi, mengungkap, dan menganalisis identitas budaya yang
berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bentuk-bentuk identitas
kultural yang terdapat dalam lagu-lagu pop daerah Manggarai.
Kata Kunci: discourse analysis, lagu, pop, Manggarai
Abstract
One of the ways Manggaraian describes the dynamics of social, politics, and cultural life are through
traditional songs that are rooted in oral tradition. It is related to the song function in the Manggarai community
as a means to pass on the values of the parents to their children. More than means of succession of traditions
and expressing the dynamics of society, these songs also display the cultural identity of Manggarai people. The
representation of identity in the form of customs, values, and norms are displayed in the lyrics of Manggarai
pop songs. Based on this phenomenon, there are two research questions, namely: what are the forms of cultural
identity shown in Manggarai pop music and how the cultural identity is displayed in the lyrics of Manggarai
pop songs. To answer these questions, discourse analysis method is used to identify, reveal, and analyze the
cultural identity associated with community life. The results of this study is the forms of cultural identity
contained in Manggarai pop songs.
Keywords: discourse analysis, song, pop, Manggarai
Prolitera: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa, Sastra, dan Budaya, 1 (1) 2018, hal. 32– 41
33
PENDAHULUAN
Tindakan para pemusik Manggarai untuk
menggambarkan situasi sosial sekaligus menyatakan
pendapat terhadap kondisi yang mereka lihat melalui
berbagai karya sebenarnya merupakan bagian integral
dari fungsi musik dalam kehidupan masyarakat
(Merriam, 1964). Lagu atau nyanyian dalam budaya
Manggarai tak hanya sebagai sarana hiburan, namun
juga untuk meneruskan nilai-nilai dari generasi yang
lebih tua kepada anak-anaknya. Penggunaan lagu-lagu
ini berhubungan dengan tidak dikenalnya budaya tulis
dalam masyarakat Manggarai. Beberapa bentuk
nyanyian tradisional seperti dere juga berisi hubungan
manusia dengan sesamanya dan alam semesta (Deki,
2011). Orang Manggarai melukiskan dinamika yang
terjadi dalam kehidupan sosial, politik, dan budayanya
melalui berbagai kesenian tradisional. Salah satu
sarana yang paling banyak digunakan adalah lagu
tradisional yang berakar dari tradisi tutur (oral
tradition).
Selain berfungsi sebagai penerus nilai-nilai dari
para orang tua kepada anak-anaknya, lagu-lagu itu
juga menampilkan identitas kultural orang Manggarai.
Representasi identitas itu berupa kebiasaan, adat
istiadat, nilai-nilai, dan norma-norma yang
membedakan masyarakat Manggarai dengan
komunitas yang berasal dari wilayah lain. Identitas
kultural itu dapat dilihat dalam lirik lagu-lagunya.
Dalam musik populer Manggarai (musik pop
Manggarai) pola-pola lagu tradisional tetap
dipertahankan. Nilai-nilai lama yang telah
direaktualisasikan sesuai dengan perkembangan jaman
menjadi tema-tema dalam teks syairnya. Pemunculan
nilai-nilai itu secara tidak langsung memperlihatkan
kondisi masyarakatnya. Berbagai perubahan dan
pergeseran orientasi hidup penduduk lokal mengubah
juga sebagian identitas kulturalnya. Kenyataan sosial
itu terekam dalam lirik-lirik lagu pop Manggarai,
sehingga musik pop Manggarai dapat dikatakan
sebagai gambaran mutakhir tentang kondisi
masyarakatnya.
Berdasarkan fungsi dan peran lagu dalam
masyarakat Manggarai serta posisi lagu-lagu pop
daerah Manggarai di tengah masyarakat, maka
terdapat dua permasalahan yang perlu dijawab,
pertama, apa bentuk-bentuk identitas kultural yang
diperlihatkan dalam musik pop Manggarai? Kedua,
bagaimana identitas kultural itu ditampilkan dalam
teks lagu-lagu pop Manggarai?
Dengan melihat permasalahan yang ada, maka
tujuan penelitian ini adalah: pertama: mengidentifikasi
identitas kultural Manggarai yang terdapat dalam teks
lagu-lagu pop Manggarai. Kedua, mengkaji dan
menganalisis bentuk-bentuk identitas kultural yang
terdapat dalam teks lagu-lagu itu. Ketiga, mengkaji
dan menganalisis identitas kultural yang ada dalam
teks itu dengan menggunakan teori discourse analysis.
Keempat, mendorong penelitian lanjutan yang
menggunakan lirik-lirik lagu sebagai obyek kajian.
Penelitian ini perlu dilakukan karena kurangnya
kajian budaya pop, terutama musik pop lokal di
Indonesia. Penelitian dengan menggunakan metode
discourse analysis dalam lirik lagu pop Manggarai
diperlukan karena melalui penelitian ini dapat
diketahui bentuk-bentuk identitas kultural masyarakat
Mnggarai yang terkandung dalam lagu-lagu itu.
Penelitian ini menargetkan identifikasi nilai-
nilai kultural yang terdapat dalam lagu-lagu pop
Manggarai yang menjadi obyek kajian. Kedua,
mengidentifikasi reaktualisasi identitas kultural
Manggarai dalam obyek kajian. Ketiga, melakukan
interpretasi terhadap hasil-hasil temuan tentang
identitas budaya Manggarai dalam lirik lagu-lagu itu.
Dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan ini, maka
kontribusi penelitian ini terhadap bidang keilmuan,
khususnya kajian musik dan teks adalah penggunaan
metode discourse analysis tidak hanya dapat
diterapkan dalam teks karya sastra, tetapi juga dalam
teks lagu-lagu. Selain itu penelitian ini juga
bermanfaat untuk bahan kajian terhadap budaya pop,
terutama lagu-lagu pop daerah.
Terdapat dua manfaat pada penelitian ini, yaitu
manfaat secara teoretis dan praktis. Manfaat
Teoretisnya adalah penelitian ini dapat dipergunakan
oleh para peneliti lain sebagai salah satu referensi
untuk mengkaji berbagai permasalahan sosial budaya
yang ada kaitannya dengan musik popular. Kedua,
penggunaan metode discourse analysis dalam kajian
lirik musik pop daerah dapat menjadi alternatif bagi
kajian musik, terutama yang berbicara dalam konteks
masyarakat lokal. Manfaat Praktis: pertama, sebagai
daerah yang berada jauh dari pusat pemerintahan
informasi mengenai Manggarai sulit diperoleh, oleh
karenanya penelitian ini berguna bagi pihak-pihak
yang membutuhkan informasi tentang masyarakat
Manggarai. Kedua, syair-syair lagu pop Manggarai
yang mencerminkan aspirasi, kondisi, dan situasi
masyarakat menjadi sumber informasi atas dinamika
Yuliantari, Sion, Galung, Endang, Agung, Representasi Identitas Kultural…
34
masyarakat, sehingga dapat menjadi masukan bagi
para stakeholder di Manggarai dalam menetapkan
kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Sementara
luaran yang diharapkan dari penelitian ini berupa
laporan penelitian dan artikel pada jurnal yang belum
terakreditasi.
Seni tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Seni
merupakan bentuk ekspresi individu maupun
kelompok di dalam masyarakat. Dinamika kehidupan
sebuah masyarakat terlihat dalam karya seninya, hal
itu menurut Merriam (1964) merupakan salah satu
fungsi seni. Selain itu, seperti terlihat dalam berbagai
peristiwa penting di dunia, seni juga dapat mengubah
sebuah kondisi dan mendorong perubahan sosial.
Musik sebagai salah satu bagian dari seni juga
mempunyai fungsi yang berhubungan dengan
masyarakatnya. Dalam kajian tentang musik rakyat,
Lomax dalam Roy (2010) mengatakan bahwa fungsi
pertama musik adalah menciptakan perasaan aman
untuk para pendengarnya dengan menyuarakan
kondisi wilayah dan kehidupan masyarakatnya.
Penggambaran kondisi wilayah dan kehidupan
masyarakat itu merupakan bagian dari konstruksi
identitas melalui hasil karya seni.
Lebih jauh dikemukakan oleh Connell &
Gibson (2003) bahwa para seniman, bahkan seluruh
komunitas dapat merepresentasikan diri mereka
sendiri dan pengalaman-pengalamannya melalui
musik, termasuk lirik-lirik yang dituliskannya, seperti
halnya karya sastra. Tujuan sebuah masyarakat
merepresentasikan dirinya melalui lagu adalah untuk
kepentingan strategis tertentu, seperti melawan
hegemoni musik transnasional, melakukan
indigenisasi dan reteritorialisasi, serta melakukan
hibriditas antara musik lokal dan global (Yuliantari,
2016).
Dalam penelitian itu dikemukakan bahwa arti
musik adalah sebuah sistem interaksi, artinya arti dari
musik baru dapat ditemukan dalam konteks hubungan
antara individu-individu dalam sebuah kelompok,
karena interpretasi terhadap musik terjadi setelah
adanya interaksi (Tekman, Boer, & Fischer, 2012).
Masyarakat Manggarai menggunakan musik untuk
berinteraksi dengan sesamanya secara tradisional, dan
konsep-konsep itu masih terdapat dalam lagu-lagu
musik pop daerah, meskipun terdapat pergeseran
orientasi dan tujuan dari pewarisan nilai-nilai budaya
dari generasi ke generasi menjadi media hiburan dan
komoditas budaya pop.
Identitas budaya yang ditampilkan dalam hasil
budaya sebuah masyarakat selalu merupakan gagasan
ideal dari masyarakatnya, sesuatu yang harus
dilakukan. Meskipun demikian realitas kehidupan
juga dituangkan dalam lirik-lirik lagu. Hal itu yang
ditampilkan dalam musik pop daerah di berbagai
wilayah, sesuai dengan pendapat Frith (2006), “The
experience of pop music is an experience of identity
[…] Music, […] symbolizes and offers the immediate
experience of collective identity” (hlm. 122-123). Pop
musik merupakan gambaran pengalaman sebuah
masyarakat, termasuk di dalamnya identitas budaya
yang dikontruksikan oleh masyarakatnya.
Dalam penelitian tentang musik, salah satu
bentuk metode analisisnya dengan menggunakan
discourse analysis. Menurut Shuker (2001) discourse
analysis adalah metode untuk menganalisis pola-pola
bahasa dan fungsi sosialnya. Metode ini berusaha
mencari asumsi-asumsi, sistem kepercayaan, dan
hubungan makna-makna yang tersembunyi dalam
wacana tertentu. Oleh sebab itu metode ini
dipergunakan dalam analisis lirik dalam lagu-lagu
karena lirik lagu adalah bahasa tampilan. Penerapan
discourse analysis secara praktis dilakukan oleh Gee
(2011). Dalam bukunya diberikan contoh-contoh
penggunaan metode ini untuk mengkaji berbagai
obyek penelitian seperti lagu, film, dan bahan kajian
teks. Buku lainnya adalah pengantar pada teori dan
praktek discourse analysis juga ditulis oleh Gee (Gee,
2011 ). Dalam buku kedua dijabarkan dasar
teoretisnya serta bagaimana hal itu diterapkan dalam
kajian ilmiah.
Beberapa penelitian tentang lagu pop daerah di
Indonesia telah dilakukan oleh para ahli. Hibriditas
musik daerah dengan alat musik Barat yang
menghasilkan musik pop daerah dilakukan oleh
Sutton (2013). Obyek kajian dalam artikel ini adalah
simponi kecapi yang berasal dari Sulawesi Selatan
dan campur sari yang berasal dari Jawa Tengah.
Keduanya mengalami hibriditas karena kepentingan
pemasaran dan penyesuaian format dengan industri
musik modern. Musik pop Manggarai disinggung
dalam sebuah bagian tulisan Kanisius Teobaldus Deki
dalam konteks tuturan sastra lisan (Deki, 2011).
Melalui tulisan ini diperoleh periodisasi musik pop
Manggarai dari awal kemunculannya sampai tahun
Prolitera: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa, Sastra, dan Budaya, 1 (1) 2018, hal. 32– 41
35
2000-an. Riset tentang lagu Minang dilakukan oleh
Barendregt (2002), berisi konsep lagu Minang sebagai
pelepas rindu terhadap kampung halaman dan
memunculkan semangat kekerabatan bagi orang-orang
Minang yang tinggal di dalam maupun luar wilayah
Sumatera Barat.
Kajian tentang hubungan industri rekaman dan
tradisi lisan dilakukan oleh Suryadi (2010). Obyek
kajiannya adalah industri musik tradisional di
Minangkabau. Persoalan yang diangkat adalah
perekaman tradisi lisan menggunakan berbagai
teknologi rekaman seperti VCD (Video Compact
Disc) dan kaset dan dampaknya terhadap popularitas
dan distribusinya dalam masyarakat. Tulisan Suryadi
(2015) lainnya merupakan bagian dari disertasinya.
Riset itu berbicara tentang pengaruh perusahaan
rekaman yang ada di daerah terhadap budaya lokal
dalam hubungannya dengan berbagai media lainnya.
Kajian tentang musik pop Indonesia
dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Bodden
(2005) tentang rap di Indonesia dan perannya dalam
akhir masa pemerintahan Orde Baru. Kajian tentang
modernitas dan musik Indonesia dilakukan oleh
(Wallach & Clinton, 2013). Berbagai persoalan music
di Indonesia dituliskan oleh keduanya, baik jenis
musik sampai sampul lagu yang merepresentasikan
genre tertentu. Penelitian Baulch tentang musik pria
dewasa (Baulch, 2010) mengamati berbagai artikel
tentang musik yang ada dalam majalah musik Rolling
Stone Indonesia (RSI). Tenyata music yang didengar
oleh para pria dewasa yang menjadi pangsa pasar
majalah itu menampilkan relasi antara genre dan kelas
sosial tertentu.
METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian
kualitatif terhadap lirik lagu-lagu pop daerah
Manggarai dengan menggunakan metode discourse
analysis. Menurut Shuker (2001) lirik lagu adalah
bahasa tampilan sehingga metode ini dapat
dipergunakan untuk menganalisis pola-pola bahasa
dan fungsi sosialnya. Selain itu metode ini juga sesuai
untuk menemukan asumsi-asumsi, sistem
kepercayaan, dan hubungan makna-makna yang
tersembunyi dalam wacana tertentu. Oleh sebab itu
metode discourse analysis dapat mengidentifikasi
identitas budaya yang termuat dalam lirik lagu dan
mengungkap serta menganalisis identitas budaya yang
ditampilkan oleh para penulis lagu pop daerah
Manggarai yang berhubungan dengan kehidupan
masyarakatnya.
Penelitian ini dilakukan dengan melalui
beberapa tahapan: pertama, tahap pengumpulan
sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam
penelitian ini adalah teks lagu-lagu pop Manggarai
dengan rentang temporal antara tahun 1970-an-1990-
an, seturut dengan periodisasi musik pop daerah
Manggarai yang dirumuskan oleh Deki (2011), yaitu
musik Manggarai yang telah menggunakan alat musik
modern. Berdasarkan periodisasi itu maka sampel
yang dipakai adalah lagu-lagu milik musikus
Manggarai yang terkenal pada periode tersebut.
Sumber sekunder berupa sumber-sumber pustaka
yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, serta majalah
baik cetak maupun online. Tahap kedua berupa tahap
olah data, pada tahap ini dilakukan pemilihan dan
pemilahan, serta pembuatan kategori serta penyusunan
catalog terhadap data-data yang diperoleh melalui
analisis terhadap isi lirik lagu-lagu yang menjadi
sampel penelitian. Tahap ketiga berupa tahap
interpretasi, yaitu kategori yang sudah disusun dalam
catalog kemudian dihubungkan dan diinterpretasikan
sesuai dengan konteks yang ada sehingga dapat
memperlihatkan identitas budaya yang berusaha
ditampilkan oleh para penulis lagu-lagu pop daerah
Manggarai.
Teknik pengumpulan data primer dalam
penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu
pemilihan sampel berdasarkan tujuan tertentu
(Arikunto, 2010). Berdasarkan teknik ini maka
diambil tiga orang penyanyi yang terkenal pada
masanya yaitu Makarius Arus untuk periode 1970-an,
Daniel Anduk pada masa 1980-an, dan Feliks Edon
pada tahun 1990-an. Dari masing-masing penyanyi
diambil 2 (dua) lagu dengan tema yang mewakili dan
sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam
penelitian. Selain sampel data primer yang telah
ditentukan di atas, sebagai referensi dipergunakan
juga sumber-sumber pustaka dari buku dan hasil
penelitian dalam jurnal-jurnal ilmiah.
Data yang berupa teks lirik lagu-lagu pop
daerah Manggarai dikumpulkan, kemudian
diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang
ditemukan dan dirumuskan selama proses
pengumpulan data. Setelah itu lirik lagu-lagu itu
dimasukkan dalam katalog yang dibuat berdasarkan
kategori tertentu. Pada tahap ini identifikasi terhadap
nilai-nilai budaya lokal dapat diperoleh. Tahap
Yuliantari, Sion, Galung, Endang, Agung, Representasi Identitas Kultural…
36
selanjutnya adalah menghubungkan masing-masing
kategori yang sesuai untuk dilakukan interpretasi. Hal
ini dilakukan untuk mengetahui identitas kultural yang
berusaha ditampilkan dalam teks lirik lagu-lagu pop
Manggarai.
REPRESENTASI IDENTITAS KULTURAL
DALAM LAGU-LAGU POP MANGGARAI
Identitas yang dimiliki oleh suatu kelompok
masyarakat ditampilkan untuk menunjukkan
perbedaannya dari masyarakat lainnya. Oleh sebab
itu, identitas perlu direpresentasikan dalam simbol-
simbol kultural yang dikenal oleh masyarakatnya.
Berdasarkan definisinya dalam ilmu sosial:
“[representation] in a more nuanced
meaning, which has
linked the practices and norms of
representing and which may,
for example, be used in the mass media, in
order to present
images of particular social groups.” (Edgar & Sedgwick, 2008, hlm. 294)
Dalam hal ini, representasi dalam media
massa yaitu lagu pop daerah yang
diperdengarkan kepada khalayak menggunakan
radio, tape recorder, maupun internet berfungsi
untuk menampilkan imaji atau gambaran tentang
kelompok sosial tertentu. Selain itu, bahasa juga
berfungsi sebagai “the representation of
thoughts in language, sekaligus “the linguistic
representation of the world of empirical
experience.” (hlm. 294) Representasi identitas kultural yang
ditampilkan melalui lagu pop Manggarai antara lain:
aktivitas masyarakat yang terlihat dalam lagu-lagu
Daniel Anduk berjudul “Daeng Tapa.” Dalam lagu
itu digambarkan aktivitas masyarakat yang sedang
membakar ubi kayu yang dalam bahasa lokal disebut
daeng. Lagu “Daeng Tapa” menunjukkan hasil bumi
lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat.
Aktivitas membakar ubi kayu menjadi penanda bagi
aktivitas masyarakat yang penting sehingga diangkat
dalam lagu, tetapi aktivitas itu bukan saja sebagai
bentuk aktivitas, melainkan bermakna untuk
menikmati hidup. Memakan ubi menjadikan
seseorang merasa menikmati hidup sekaligus
menunjukkan kemauan untuk bekerja keras demi
kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhannya.
Lagu itu juga menunjukkan bahwa ubi kayu
menjadi representasi dari pola kehidupan
masyarakat. Bahasan pertama, menunjuk daerah
tertentu di Manggarai Barat, yaitu Kempo. Hal itu
terlihat dalam teks, “Daeng kempo daeng o,” yang
berarti ubi yang berasal dari wilayah Kempo.
Pemilihan wilayah Kempo sebagai lokasi dapat
berhubungan dengan kondisi wilayah yang subur.
Hal ini terlihat dalam bagian lain teks yaitu, “lole
daeng daeng e.” Kesuburan itu menimbulkan
kenikmatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah
itu. Kata, “daeng a wusak koe tuka’g daeng e,”
menunjukkan makanan dapat mendukung kehidupan
dan menjamin kesejahteraannya.
Selain menampilkan hal bersifat harafiah,
terdapat pula beberapa pesan secara filosofis seperti:
“Neka na’as tombo data Nyia nuk nai rum,” dan
“Neka imbis tombo nipi. Nyia nuk nai rum.” Dari dua
teks itu dapat terlihat bahwa masyarakat Manggarai
mengidealkan kehidupan yang harmonis dengan
masyarakat sekitar. Omongan orang jangan menjadi
penghalang relasi sosial, sesuatu yang telah terjadi
tidak perlu dipersoalkan. Demikian juga kepercayaan
yang tidak pada tempatnya dan cenderung kontra
produktif seperti pembicaraan tentang mimpi. Hal-
hal seperti itu menghambat relasi sosial dan aktivitas
individu, sehingga setiap orang harus berpegang
teguh terhadap prinsip dan hati nuraninya dalam
menghadapi berbagai persoalan.
Bentuk identitas lainnya yang ditampilkan
adalah hubungan kekerabatan. Relasi terdekat
dengan anggota keluarga ini terdapat dalam lagu
“Katarina” oleh Makarius dan Daniel Anduk dengan
lagu “Hop Hau Ngom,” dan Feliks Edon dengan lagu
“So Aso.” Sistem kekerabatan pada lagu “Katarina”
terlihat pada kata-kata,
Weta ge...a...
Ee,,,e,,,e a
Kata weong na’i
ge...e...e
Ca’it weta leca ho’o
gee....
Gelang ka’t benta’n
Saudariku
Ee….e….e a
Kata sedih hati ku
Saudari tunggal
Cepat dipanggil Tuhan
Adikku tersayang
Cepat sekali pergi
Prolitera: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa, Sastra, dan Budaya, 1 (1) 2018, hal. 32– 41
37
gea..
Cait weta momang
ho’o gee....
Gelang ka’t mora’n ge
a...
Pada lagu di atas ditunjukkan bahwa sang
tokoh dan Katarina mempunyai hubungan
kekerabatan sebagai kakak dan adik. Sebutan “weta”
menunjukkan bahwa Katarina adalah saudara
perempuan. Kata “weta leca” menyatakan bahwa
Katarina adalah saudari satu-satunya, sehingga
sesuai dengan teks keseluruhan lagu, kematiannya
membawa kesedihan mendalam bagi saudara laki-
lakinya.
Selain pada teks di atas, identifikasi
kekerabatan juga terdapat dalam syair:
Kata weong nai ge....e...e
Awo Bea Ngawang.....
Awo Bea Ngawang
Bea Ngawang rei anak’n
e.....
Weta ge.....a......
Kata merana hati ku
Di Bea Ngawang
Di Bea Ngawang
Bea Ngawang tanya
anakmu
Adikku
Di lagu itu juga menampilkan bahwa
Katarina telah berkeluarga dan memiliki anak yang
tinggal jauh dari orang tua. Kepergian Katarina ke
rumah sakit yang berada di Goloworok
menyebabkan anak-anaknya menderita dan selalu
bertanya-tanya tentang kondisinya. Berdasarkan teks
lagu di atas, ditunjukkan juga bila sang tokoh, yaitu
paman dari anak-anak Katarina, mempunyai
hubungan yang erat dengan keponakan-
keponakannya, karena dalam budaya Manggarai,
keluarga lelaki sebagai pemberi istri (wife giver)
mempunyai kewajiban untuk melindungi saudara
perempuan dan keturunannya (Deki, 2011).
Relasi kekerabatan juga terdapat dalam lagu
“Hop Hau Ngom,” tulisan Daniel Anduk. Lagu itu
menunjukkan peran ayah sebagai tokoh sentral
dalam keluarga. Anak dalam lagu itu merasa
kehilangan ketika ayahnya meninggal dunia karena
kehilangan tokoh yang menjadi panutan dan
pelindung keluarga. Posisi itu tidak tergantikan oleh
orang lain. Hal ini dapat terlihat dalam bait,
Ho’o hau ngom ho kini engkau telah pergi
ema.....
Ho’o hau ngom go
ema ge....
Toe kin pung ca’n
laki anak
imi amas deming
ema ata kami ga
Ho;o hau ngom ho
ema....
Ho’o hau ngom go
ema ge...
Toe ki pung ca’n laki
anak
imi amas deming
ema ata kami ga
ayah
kini engkau telah pergi
ayahku
belum satu pun anakmu
yang ambil istri
malu kami percayakan
ayah orang lain
kini engkau telah pergi
ayah
kini engkau telah pergi
ayahku
belum satu pun anakmu
yang menikah
malu kami percayakan
ayah orang lain
Selain memiliki peran sentral yang tidak
tergantikan, kesedihan yang ditimbulkan oleh
kehilangan orang tua menyebabkan kehidupan sang
tokoh menderita. Tokoh dalam lagu ini
mendefinisikan kehilangan itu sebagai kemalangan
yang menimpa hidupnya dan berpengaruh terhadap
nasibnya di dunia.
Ho’o hau ngom go
ema ge...
Toe di pung laki anak
dading’m
kanang ata pait ami
musi mai tenang
ema
kini engkau telah pergi
ayahku
belum satu pun anakmu
yang ambil istri
duka selalu menimpa
kami jika ingat ayah
Hal lain yang terlihat dalam lagu ini adalah
posisi ayah yang penting dalam kehidupan sebuah
keluarga. Kedudukan itu tidak tergantikan oleh orang
lain, meskipun termasuk kerabat atau kenalan. Peran
penting ayah ini berhubungan dengan relasi sosial
dan kultural dengan masyarakat di lingkungannya.
Ayah menjadi kepala keluarga, pemimpin, dan
penghubung antara anak-anaknya dengan generasi
sebelumnya. Peran ini terlihat dalam teks:
Ho’o hau ngom ho
ema.....
Ho’o hau ngom go
ema ge....
Toe kin pung ca’n laki
anak
imi amas deming ema
kini engkau telah pergi
ayahku
kini engkau telah pergi
ayahku
belum satu pun anakmu
yang ambil istri
kebingungan kami
Yuliantari, Sion, Galung, Endang, Agung, Representasi Identitas Kultural…
38
ata kami ga mengharapkan orang tua
orang lain
Selain lagu di atas, system kekerabatan juga
terdapat dalam lagu Daniel Anduk lainnya, yaitu
“Mose Lalo.” Dalam lagu yang berbicara tentang
seorang pemuda yang hidup sebatangkara,
ditunjukkan bahwa keluarga sebagai pusat kehidupan
kekerabatan dalam masyarakat Manggarai
mempunyai dimensi konflik. Hal ini dapat
disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan,
ketidakharmonisan dalam keluarga, anak di luar
perkawinan, atau berbagai persoalan lainnya. Dalam
konteks lagu ini, anak lelaki dalam sebuah
perkawinan ditinggalkan oleh keluarganya karena
faktor penikahan yang tidak harmonis. Hal ini
terlihat dalam teks:
deeee mose lalo
deeee mose lalo
lalo ledong one leso
lalo pencang one
wejang
deee mose hanang
deee mose hanang
mose hanang kaeng tana
lingi-lengot kaeng lino
kawe ema agu ameee
coo ame toe haeng
kawe laku ende bo ende
toe repeng
mori baeng aku ta deee
mori baeng anak meee
Hidup sebatang kara
Hidup sebatang kara
Sebatang kara hidup
sengsara
Ditinggal sendirian
Hidup sendiri
Hidup sendiri
Hidup sendiri di dunia
Sunyi senyap tinggal di
dunia
Mencari bapa dan sanak
saudara
Mencari sanak saudara
tidak ada
Kucari ibu, tapi ibu
tidak kutemukan
Tuhan kasihanilah aku
Tuhan kasihanilah
anakmu
Dalam lagu di atas, sang anak laki-laki
berusaha mencari sanak-saudara atau keturunan dari
ayahnya, tetapi tidak ditemukannya seperti dalam
teks, “kawe ema agu ameee, coo ame toe haeng.”
Demikian juga ketika mencari ibu dan keluarga
besarnya, “kawe laku ende bo ende toe repeng.”
Ekspoitasi kesedihan dalam lagu di atas
menjadi tujuan utama, sehingga menghilangkan
realitas, bahwa di Manggarai eratnya system
kekerabatan menyebabkan anak-anak menjadi
tanggung-jawab bersama seluruh klan. Ketiadaan
seorang ayah atau ibu dapat digantikan secara
fungsional oleh paman atau bibi seorang anak atau
kakek dan neneknya. Kondisi seorang anak seperti
dalam lagu di atas termasuk hal yang jarang terjadi
dalam realitas kemasyarakatan.
System kekerabatan juga terdapat pada lagu
“So Aso.” Dalam lagu ini ditampilkan keluarga besar
yang berhubungan dengan sang tokoh. Hal itu
terlihat dalam teks di bawah ini:
So inang so amang so 4x
Sooo inang sooo amang
So aso inang so aso
amang soo2x
Inang dalu cibal le
Amang dalu lamba ee
Siri sok ee toe pening one
peti manuk kiokok
kiokok kiii oo
So inang so amang so 4x
Sooo inang sooo amang
So aso inang so aso
amang soo2x
Hai bibi hai paman
Hai bibi hai paman
Hai bibi hai paman
Bibi dalu Cibal
Paman dalu
Lambaleda
Bisik-bisik tidak
punya ayam
peliharaan
Hai bibi hai paman
Hai bibi hai paman
Hai bibi hai paman
Melalui lagu ini Feliks Edon
menggambarkan hubungan kekerabatan di luar
keluarga inti. Melihat sebutannya, yaitu “Inang” dan
“Amang” hal itu mengindikasikan hal yang serupa
dengan lagu “Katarina,” yaitu pentingnya posisi
“anak rona” dalam system kekerabatan di daerah ini.
Anak rona sebagai wife giver berperan penting
menentukan posisi seseorang dalam masyarakat.
Penyebutan lokasi dalam konteks keluarga ini
menunjukkan banyaknya hubungan kekerabatan
yang dimiliki baik yang berasal dari Cibal maupun
yang dari Lambaleda.
Selain hubungan kekerabatan hal lain yang
dikemukakan di sini adalah kritik terhadap kebiasaan
masyarakat tertentu yang menghabiskan waktunya
dengan berbisik-bisik atau bergossip sehingga
menghabiskan waktu. Akibat dari perbuatan itu
adalah tidak tercukupinya kebutuhan hidup. Hal ini
tercermin dalam syair lagu, “Siri sok ee toe pening
one peti manuk.” Kebiasaan bergossip membuat
keluarga paman dan bibi sang tokoh tidak dapat
memelihara ayam.
Bagi masyarakat Manggarai hewan
peliharaan sangat dibutuhkan karena berguna untuk
kebutuhan sehari-hari maupun acara adat tertentu.
Prolitera: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa, Sastra, dan Budaya, 1 (1) 2018, hal. 32– 41
39
Ayam berguna untuk berbagai ritus adat seperti teing
hang, memberi makan arwah nenek moyang, we’e
mbaru, selamatan pendirian rumah, acara pergantian
tahun, dan lain sebagainya. Keluarga yang tidak
punya hewan peliharaan membutuhkan biaya lebih
besar untuk mengadakan hewan kurban.
Terdapat identifikasi tempat tertentu yang
berada di wilayah Manggarai seperti terlihat dalam
lagu “Daeng Tapa” yaitu Kempo, seperti yang
terdapat dalam syair, “Daeng kempo daeng o”.
Dalam hal ini wilayah Kempo ditunjukkan sebagai
daerah yang subur sehingga menghasilkan ubi kayu
yang enak dan dalam jumlah besar sehingga
menyejahterakan masyarakat seperti dalam teks,
“De....daeng ngenggo lako na”.
Dalam lagu “Katarina” tempat yang
ditampilkan adalah Lida, Goloworok, Bea Nawang.
Lida menunjuk lokasi tempat tinggal sang tokoh
yang berada di sebelah barat dari Goloworok. Hal ini
terdapat dalam teks, “Sale Barat Lida..... Sale Barat
Lida...Barat Lida re’i inang’m....e”. Goloworok
adalah tempat di mana adik perempuan satu-satunya
itu di rumah sakit, hal itu terdapat dalam teks “Eta
Golo Worok..... Eta Golo Worok....Golo Worok do
tombo’m e.” Sementara Bea Ngawang adalah tempat
tinggal anak-anak Katarina, hal ini terlihat dari kata-
kata “Awo Bea Ngawang..... Awo Bea Ngawang, Bea
Ngawang rei anak’n e.” Pemilihan Goloworok dan
Lida tidak mempunyai konotasi tertentu selain
menunjukkan jauhnya lokasi itu dengan sang tokoh
sehingga menimbulkan kepedihan ketika Katarina
meninggal dan sang tokoh tidak dapat
mengunjunginya lebih awal. Sementara Bea Nawang
menunjukkan jika anak-anak Katarina tinggal di
tempat berbeda karena ibunya harus tinggal di rumah
sakit seperti terdapat dalam teks, “Awo Bea
Ngawang, Bea Ngawang rei anak’n e.”
Dalam lagu “So Aso” karangan Feliks Edon,
lokasi yang ditunjuk meliputi dua wilayah yaitu
Cibal dan Lamba. Hal ini dapat dilihat dalam teks,
“Inang dalu cibal le, Amang dalu lamba ee.” Lagu
ini menunjukkan banyaknya kerabat yang dimiliki
oleh sang tokoh. Di sini Cibal dan Lamba(leda)
adalah dua dalu yang cukup luas, sehingga
mengindikasikan hubungan dengan orang yang
berasal dari berbagai wilayah.
Dalu adalah system pemerintahan lokal yang
setara dengan kecamatan dalam stuktur
pemerintahan pusat. Berbeda dengan kecamatan
yang condong bersifat administratif, kedaluan
bersifat geopolitik. Pemerintah kedaluan lebih
mandiri dan mempunyai otoritas yang besar terhadap
wilayahnya. Hal ini disebabkan karena dalu
bertanggungjawab terhadap wilayahnya secara
ekonomi, sosial, dan politis terhadap pimpinan yang
lebih tinggi, yaitu raja (Toda, 2011). Kedaluan Cibal
dan Lamba(leda) mempunyai kekuasaan politik yang
besar di Manggarai sebelum kedatangan Belanda
pada abad XIX. Kekuasaan keduanya surut setelah
pemerintah Hindia Belanda memaklumkan system
pemerintahan baru yang berpusat di Ruteng.
Pada lagu “Ngkiong Ta” tidak disebutkan
lokasi secara spesifik, tetapi himbauan untuk
menjaga lingkungan diberlakukan secara umum
karena lokasi yang disebutkan tidak bersifat
definitive. Hal itu terdapat dalam teks di bawah ini:
Senget Runing
Ngkiong Neka Poka
Puar
Boto Mora Usang
Lawa Eee Eee
Kudut Kembus
Tedeng Wae Teku
Aku Mboas Wae
Woang Dite Gaa
Runing Ngkong,
Ngkong Ee Ie Aa
Aoo Uoo Uoa
Ngkiong Eee
Senget Runing
Ngkiong Neka Tapa
Satar
Dengar suara Ngkiong
jangan membabat hutan
Agar tidak kurang hujan
Supaya mata air tetap
mengalir
Tetap mengalir air
sumber kehidupan
Suara ngkiong Ngkong
Ee Ie Aa
Aoo Uoo Uoa Ngkiong
Eee
Dengar suara Ngkiong
jangan membakar semak-
semak
Dalam teks di atas lokasi yang disebutkan
adalah puar (hutan), wae teku (mata air), dan satar
(semak-semak). Selain itu disebutkan juga poco atau
hutan belantara. Keempat lokasi itu terdapat di
seluruh Manggarai Raya dan identik dengan wilayah
Manggarai yang subur.
Penempatan lokasi-lokasi dalam lagu
Manggarai tidak hanya terdapat dalam lagu pop,
tetapi hal itu terdapat juga dalam genre lagu lain
seperti rap. Penggunaan tempat dalam rap Manggarai
juga menjadi bagian untuk menunjukkan identitas
para rapper (Yuliantari A. P., 2015). Jika para
rapper menggunakan tempat sebagai usaha
menunjukkan kredibilitasnya dalam ruang dan
Yuliantari, Sion, Galung, Endang, Agung, Representasi Identitas Kultural…
40
tempat (Yuliantari A. P., 2016), para penyanyi pop
daerah Manggarai menggunakan tempat sebagai
representasi dari berbagai kepentingan seperti jarak,
kemakmuran suatu tempat, dan geopolitics.
Keanekaragaman representasi tempat dalam pop
Manggarai disebabkan karena tidak adanya konvensi
fungsi ruang dan tempat seperti dalam lagu rap
Manggarai.
Bagian lain yang disebutkan dalam lagu pop
Manggarai adalah pentingnya menjaga kelestarian
lingkungan hidup. Dalam teks lagu “Ngkiong Ta,”
lokasi yang disebutkan adalah puar (hutan), wae teku
(mata air), dan satar (semak-semak). Tiga lokasi ini
berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat
Manggarai yang agraris. Hutan berfungsi untuk
resapan air sehingga sumber mata air dapat terus
hidup. Hal ini penting karena masyarakat di desa
menggantungkan air minum dari mata air, bukan
menggunakan sumur. Demikian juga semak-semak
harus dijaga agar tidak terjadi tanah longsor. Hutan
juga menjadi sumber kayu bakar. Pembabatan hutan
dapat menyebabkan hancurnya ekologi. Termasuk
hilangnya hewan-hewan penghuni hutan yang
berperan membantu petani memberantas hama
tanaman, seperti ular dan burung hantu yang menjadi
lawan tikus.
Dalam teks lainnya disebutkan “Dere Ngkiong
Taaa Ngkiong Le Poco.” Meskipun mempunyai
terjemahan yang sama antara puar dan poco tetapi
pada kenyataannya keduanya.
PENUTUP
Lagu atau nyanyian dalam budaya Manggarai
tak hanya sebagai sarana hiburan, namun juga untuk
meneruskan nilai-nilai dari generasi yang lebih tua
kepada anak-anaknya. Penggunaan lagu-lagu ini
berhubungan dengan tidak dikenalnya budaya tulis
dalam masyarakat Manggarai.
Analisis terhadap lagu-lagu pop daerah
Manggarai dapat dilakukan dengan menggunakan
metode discourse analysis. Penggunaan metode ini
memungkinkan untuk mengupas identitas kultural
masyarakat yang ditampilkan dalam teks-teks lagu
pop daerah. Identitas ini direpresentasikan dengan
menggunakan lagu karena meluasnya penggunaan
media massa baik audio maupun visual.
Identitas kultural masyarakat yang semula
diwariskan dengan menggunakan cara konvensional,
yaitu berbagai bentuk kesenian tradisional kemudian
diganti oleh media modern. Melalui media yang baru
representasi identitas itu dapat menjangkau berbagai
kalangan di lokasi yang lebih luas, sehingga teks lagu
pop daerah menjadi media efektif untuk
merepresentasikan identitas kultural orang Manggarai.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu
Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Barendregt, B. (2002). The sound of longing for
home: Redefining a sense of community
through Minang popular music. Bijdragen
tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 158
(2002), no: 3, Leiden, 411-450.
Baulch, E. (2010). Music for the Pria Dewasa:
Changes and Continuities in Class and Pop
Music Genre. Journal of Indonesian Social
Sciences and Humanities Vol. 3, 2010, pp.
99-130, 99-130.
Bodden, M. (2005). Rap in Indonesian Youth Music
of the 1990s: ‘‘Globalization,’’ ‘‘Outlaw
Genres,’’ and Social Protest. Asian Music:
Summer/Fall 2005, 1-26.
Connell, J., & Gibson, C. (2003). Sound Tracks:
Popular Music, Identity, and Place. London:
Routledge.
Davis, H. (2004). Stuart Hall. London: SAGE
Publication.
Deki, K. T. (2011). Tradisi Lisan Orang Manggarai:
Membidik Persaudaraan Dalam Bingkai
Sastra. Jakarta: Parrhesia.
Edgar, A., & Sedgwick, P. (2008). Cultural Theory:
The Key Concepts. London: Routledge.
Frith, S. (2006). Music and Identity. In S. Hall, & P.
d. Gay, Questions of Cultural Identity (pp.
108-127). London: SAGE Publications Inc. .
Gee, J. P. (2011 ). An introduction to Discourse
Analysis: Theory and Method. London:
Routledge.
Gee., J. P. (2011). How to do Discourse Analysis : a
Toolkit . London: Routledge.
Merriam, A. P. (1964). The Anthropology of Music.
Evanston: Northwestern University Press.
Prolitera: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa, Sastra, dan Budaya, 1 (1) 2018, hal. 32– 41
41
Procter, J. (2006). Stuart Hall. New York:
Routledge.
Roy, W. G. (2010). Reds, Whites and Blues: Social
Movement, Folk Music, and Race in the
United States. Princeton: Princeton
University Press.
Shuker, R. (2001). Popular Music: The Key
Concepts. New York: Routledge.
Suryadi. (2010). The Impact of the West Sumatran
regional recording industry on Minangkabau
oral literature. Wacana, Vol. 12 No. 1 (April
2010), 35—69.
Suryadi. (2015). The Recording Industry and
“regional” Culture in Indonesia: The case of
Minangkabau. Wacana Vol. 16 No. 2 , 479-
509.
Sutton, R. A. (2013). Musical Genre and Identity in
Indonesia: Simponi Kecapi and Campur
Sari. Asian Music, Volume 44, Number 2,
Summer/Fall 2013, 81-94.
Tekman, H. G., Boer, D., & Fischer, R. (2012).
Values, Functions of Music, and Musical
Preferences. Proceedings of the 12th
International conference on Music
Perception and Cognition and the 8th
Triennial Conference Of the European
Society for the Cognitive Science of Music
(hlm. 372-377). Thessaloniki: Tanpa
Penerbit.
Toda, D. N. (2011). Manggarai Mencari
Pencerahan Historiografi. Ende: Nusa
Indah.
Wallach, J., & Clinton, E. (2013). History,
Modernity, and Music Genre in Indonesia:
Popular Music Genres in the Dutch East
Indies and Following Independence. Asian
Music Vol. 44 Number 2 Summer/ Fall 2013,
3-23.
Yuliantari, A. P. (2015). Ruteng is da City:
Representasi Lokalitas dalam Musik Rap
Manggarai. Resital Vol. 16 No. 2 Agustus
2015, 65-74.
Yuliantari, A. P. (2016). Hibriditas Budaya
Amerika: Studi Transnasional Musik Rap
pada Masyarakat Manggarai di Nusa
Tenggara Timur. Yogyakarta: Universitas
Gadjah Mada, unpublished dissertation.