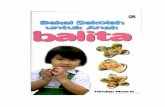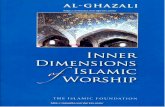resensi buku
-
Upload
iainsalatiga -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of resensi buku
RESENSI BUKU
ISLAMIC STUDI PENDEKATAN DAN METODE
Resensi Ini Disusun Sebagai Pemenuhan Tugas Mata KuliahMetodelogi Studi Islam yang Diampu Oleh Dr. Zakiyuddin
baidhaw.
Oleh:
Muhammad Choirurohman (215-13-010)
JURUSAN ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHLUHUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
1
IAIN SALATIGA
2015
IDENTITAS BUKU
Peresensi : Muhammad Choirurohman
Judul Buku : ISLAMIC STUDEIS PENDEKATAN DAN METODE
Penulis : Zakiyuddin Baidhawy
Penerbit : Insan Madani
Ceakan : cetakan Pertama April, 2011
Tebal : 310 halaman
PENULIS
Zakiyuddin Baidhawy lahir diIndramayu, Jawa Barat. Kini tinggal
diSolo. Menyelesaikan studi S-1 pada Fakultas Agama Islam
(Perbandingan Agama) Universitas Muhammadiyah Surakarta (1994). Pernah
nyantri diPondok Hajjah Nuriyah Shabran (1990-1994). StudiS-2 pada
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), dan S-3 pada
Universitas yang sama (2007). Staf Edukatif pada Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri(STAIN) Salatiga, Peneliti pada Pusat Studi Budaya dan
Perubahan Sosial UMS, Associate pada Maarif Institute for Culture and
Humanity.
PENDAHULUAN
2
Buku ``Islamic studies pendekatan dan metode`` ini hadir sebagai
solusi kebimbangan masyarakat, serta member penjelasan kepada
masyarakat kontemporer akan ruang lingkup studi islam, didalamnya
berisi dari bab yang sederhana, tentan penjelasan/pengertian
metodelogi studi islam, sampai yang terperinci, tentang ruang lingkup
kajian, sejarah perkembangan kajian, model-model kajian dari yang
model kajian ilmu kalam, tasawof, hermeneotika, ushul fiq dan fiqih,
filsafat, dan pendidikan.
SINOPSIS
BAB 1
PENGERTIAN DAN METODOLOGI STUDI ISLAM
A. Pengertian Studi Islam
Istilah “Islamic Studies” atau Studi Islam kini telah dipergunakan
dalam jurnal-jurnal profesional, departemen akademik, dan lembaga-
lembaga perguruan tinggi yang mencakup bidang pengkajian dan
penelitian yang luas, yakni seluruh yang memiliki dimensi“Islam” dan
keterkaitan dengannya. Rujukan pada Islam, apakah dalam pengertian
kebudayaan, peradaban, atau tradisi keagamaan, telah semakin sering
dipakai dengan munculnya sejumlah besar literatur dalam berbagai
bahasa Eropa atau Barat pada umumnya yang berkenaan dengan paham Islam
politik, atau Islamisme. Literatur-literatur tersebut berbicara
tentang perbankan Islam, ekonomi Islam, tatanan politik Islam,
demokrasi Islam, hak-hak asasi manusia Islam, dan sebagainya. Sejumlah
buku-buku terlaris sejak 1980an berhubungan dengan
3
judul-judul “Islam” dan hal-hal yang berkaitan dengan kata sifat
“Islami”, yang menunjukkan betapa semua itu telah diistilahkan dengan
sebutan “Islamic Studies” didunia akademik.
BA B 2
RUANG LINGKUP OBJEK KAJIAN STUDI ISLAM
A. Pengalaman Keagamaan dan Ekspresinya
Setiap kajian ilmiah menghendaki objek sebagai prasyarat utama.
Kejelasan objek memudahkan para pengkaji membuat batasan akan ruang
lingkup suatu studi. Studi Islam sebagai kajian ilmiah pada intinya
adalah upaya mencari pemahaman mengenai hakikat agama, bukan sekadar
fungsi agama. Hakikat agama itu terletak pada pengalaman keagamaan.
Joachim Wach (1958) menjelaskan beberapa kriteria mengenai pengalaman
keagamaan. Pertama, pengalaman keagamaan merupakan suatu respon
terhadap apa yang dialami sebagai Realitas Ultim (the Ultimate
Reality). Realitas Ultim disini artinya sesuatu yang “mengesankan dan
menantang kita”. Pengalaman ini melibatkan empat hal, yaitu asumsi
tentang adanya kesadaran, yakni pemahaman dan konsepsi; respon
dipandang sebagai bagian dari perjumpaan; pengalaman tentang Realitas
Ultim mengimplikasikan relasi dinamis antara yang mengalami dan yang
dialami; dan kita perlu memahami karakter situasional dari pengalaman
keagamaan itu sendiri dalam suatu konteks tertentu.
Kedua, pengalaman keagamaan itu harus dipahami sebagai suatu respon
menyeluruh terhadap Realitas Ultim, yaitu pribadi yang utuh yang
melibatkan jiwa, emosi dan kehendak sekaligus. Karenanya, pengalaman
keagamaan terdiri dari suatu hirarki tiga unsur, yaitu intelektual,
afeksi, dan kesukarelaan.
4
Ketiga, pengalaman keagamaan menghendaki intensitas, yaitu suatu
pengalaman yang sangat kuat, komprehensif, dan mendalam. Para tokoh
pembawa agama sepanjang masa dan dimanapun telah memberikan kesaksian
tentang intensitas ini baik dalam pikiran, ucapan maupun tindakan.
Dalam Islam misalnya, antusiasme yang bergairah terhadap Allah telah
membangkitkan spiritualitas NabiMuhammad, dan para tokoh lainnya
seperti Rabiah al-Adawiyah, al-Hallaj, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hanbal, al-
Afghani, dan sebagainya.
Keempat, pengalaman keagamaan sejati selalu berujung pada tindakan. Ia
melibatkan imperatif, sumber motivasi dan tindakan yang kuat. Praktik-
praktik dan tindakan-tindakan kita dalam keseharian merupakan bukti
nyata bahwa kita seorang yang beragama sejati.
Empat kriteria tersebut menggaris bawahi bahwa pengalaman agama sejati
merupakan pengalaman batin dari perjumpaan manusia dan pikiran manusia
dengan Tuhan. Karena pengalaman batiniah itu sifatnya personal dan
unik, maka pengalaman keagamaan itu sendiri sulit untuk dijadikan
sebagai objek langsung dari kajian ilmiah dalam Studi Islam.
BAB 3
SEJARAH PERKEMBANGAN STUDI ISLAM
Studi Islam mulai muncul pada abad ke-9 diIrak, ketika ilmu-ilmu agama
Islam mulai memperoleh bentuknya dan berkembang didalam sekolah-
sekolah hingga terbentuknya tradisi literer dikawasan Arab masa
pertengahan. Studi Islam bukan hanya berjalan didalam peradaban Islam
itu sendiri bahkan juga menjadi fokus diskusi dinegara-negara Barat.
Bahkan, sebelum kemunculan Islam pada abad ke-7, orang-orang Arab
sudah dikenal oleh bangsa Israel dan Yunani Kuno serta para pendiri
5
gereja. Pandangan orang-orang Eropa tentang Islam sepanjang masa
pertengahan diambil dari konstruk Injili dan teologis. Mitologi,
teologi, dan missionarisme menyediakan formulasi utama tentang apa
yang diketahui gereja mengenai Muslim sekaligus alasan-asalan bagi
perkembangan wacana resmi tentang Islam. Secara mitologis, Muslim
dipandang sebagai orang Arab, Sarasen, yang merupakan keturunan
Ibrahim melalui Siti Hajar dan putranya Ismail.
Richard C. Martin dengan gamblang menjelaskan fase-fase perkembangan
Studi Islam, antara lain sebagaiberikut:
Fase Pertama (800-1100), masa dimana banyak bermunculan polemik
teologis antara Muslim, Kristen dan Yahudi. Mitos dan legenda Yahudi-
Kristen menyebutkan kemunculan kaum monoteistik Arab non-Yahudi dan
Kristen pada abad ke-7. Polemik teologis sering terjadi dalam ruang
public atau dalam audiensi Khalifah atau pejabat resmi negara, yang
dilakukan oleh para mutakallimun. Kaum Yahudi dan Kristen sebagai
kelompok atau ahlu zimmi berpartisipasi dalam ritual-ritual sosial
diskursus dan perdebatan publik dengan kaum Muslim. Ini semua
membutuhkan banyak pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam, dengan
tujuan hanya untuk menolak ajaran tersebut.
Orang-orang Yahudi dan Kristen Eropa berupaya untuk mengkonstruk
pemahaman mereka sendiri tentang Islam. Karena kurangnya pengalaman
kerjasama dan perjumpaan dikalangan mereka ketika hidup dibawah
kekuasaan Islam diTimur, Gereja Romawimemandang Islam sebagai“yang
lain”, asing, musuh Kristen yang harus dikonversi melalui kampanye
militer dan missionaris.
Selama empat abad kemudian hingga awal Perang Salib, orang-orang Eropa
hidup dalam kebodohan tentang agama dan penduduk yang hidup bersebelah
6
dengan mereka diSpanyol. Suku-suku Jerman, orang Slavia, Magyar, dan
gerakan-gerakan bidah seperti Manicheanisme, melihat Islam sebagai
salah satu musuh yang mengancam kerajaan Kristen. Sejak awal Perang
Salib hingga abad ke-11, nama Muhammad dikenal negatif dikalangan
Eropa. Tafsir-tafsir keagamaan Kristen mengidentikkan bangsa Sarasen
dengan bangsa Ismail, keturunan Ibrahim dariHajar.
BAB 4
MODEL PENDEKATAN KAJIAN TEKS-TEKS ISLAM: STUDI AL-QUR’AN
Studi Islam dalam pengertiannya yang sempit, sebagaimana telah
dijelaskan dalam bab I, adalah suatu disiplin intelektual dan
keagamaan tradisional. Mengikuti pengertian ini, maka kajian-kajian
atas teks-teks keislaman membentuk ruang lingkup inti dari Studi
Islam. Kajian-kajian berbasis pada teks-teks, sebagaimana dikenal
dalam tradisi bayani, menekankan prisma teks sebagai cara untuk
memahami hakikat Islam. Karena itu, kajian semacam ini menekankan
perhatian pada teks-teks suci keislaman utamanya Al-Qur’an dan hadis,
juga karya-karya intelektual klasik yang berhubungan erat dengan dua
sumber ajar-an tersebut.
Dalam sejarah perkembangan peradaban dan pemikiran Islam, dikenal
sejumlah cabang keilmuan tradisional Islam yang meliputi antara lain
ulum al-Qur’an dengan seluruh ramifikasi-nya, tafsir al-Qur’an, ulum
al-hadis lengkap dengan semua percabangannya, ilmu kalam, tasawuf,
fikih, dan usul fikih, dan lain-lain. Cabang-cabang keilmuan ini
merupakan jasa para pengkaji Muslim atas tradisi tekstual keagamaan
mereka dan telah melahirkan khazanah intelektual yang sangat kaya.
Karena objek kajian studi Islam tradisional ini adalah teks-teks
keagamaan dan karya-karya yang berkaitan dengannya, maka metode dan
7
pendekatan yang dipergunakan oleh komunitas ilmiah dikalangan mereka
pun meliputi metode dan pendekatan tekstual (bayani).
BAB 5.
MODEL KAJIAN TEKS-TEKS KEISLAMAN: STUDI HADIS
Hadis merupakan sumber utama Islam kedua setelah Al- Qur’an. Karena
itu, perdebatan tentang hadis bukanlah suatu yang mengejutkan hingga
saat ini terus terjadi. Pada akhir abad ke-20, studi hadis mencatat
kemajuan yang berarti dan semakin banyak memperoleh perhatian dari
kalangan dunia Islam dan Barat. Ini disebabkan penemuan-penemuan
banyak sumber baru dan perkembangan dalam bidang metodologi. Banyak
manuskrip hadis pada masa-masa awal diterbitkan dan memperoleh bahasan
dari para sarjana. Beberapa sumber hadis yang baru mencakup kitab
Musannaf (11 volumes, Beirut 1391/1972) karya `Abdur-Razzaq ibn Hammam
As-San`ani (w. 211/827), Al-Kitab al-Musannaf fi al-Ahadith wa al-
Athar (15 volumes, Hyderabad 1386/1983) karya Ibn AbiShaybah (w.
235/849), dan Tarikh al-Madinah al-Munawwarah (4 volumes., Jeddah,
tth.) karya `Umar ibn Shabba.
Tiga sumber ini dan banyak lainnya dipandang sebagai temuan penting
dalam bidang wacana hadis. Diantara metodologi baru yang berkembang
dalam studihadis adalah dua pendekatan yang dapat dibedakan: Pertama,
analisis isnad terhadap hadis-hadis ahad, demikian Harald
Motzki(1992) menyebutnya, yang terbukti menjadi alat penelitian yang
sangat kuat. Metodologi ini secara luas telah diterapkan oleh sarjana
Belanda GHA. Juynboll (1989). Kedua, pendekatan yang fokus pada
analisis teks (matn) hadis yang dikembangkan melalui penyelidikan
varian teks-teks hadis, dan kombinasi pendekatan analisis teks dan
8
analisis isnad. Beberapa diantara yang menggunakan pendekatan ini
ialah Gregor Schoeler dan Motzki(1992).
Wael B. Hallad dariMcGill University menyatakan bahwa sejak Joseph
Schacht menerbitkan karya monumentalnya pada 1950, wacana ilmiah
tentang masalah ini(persoalan otentisitas hadis) telah tersebar luas.
Tiga kelompok sarjana dapat diidentifikasi disini antara lain: mereka
yang berusaha untuk menguatkan analisis Schacht dan melampaui
analisisnya; mereka yang berupaya menolak analisis Schacht; dan mereka
yang berupaya mencari jalan tengah, membuat sintesis antara dua
pendapat diatas. Dalam kelompok pertama antara lain John Wansbrough
dan Michael Cook; kelompok kedua antara lain Nabia Abbott, F. Sezgin,
M. Azami, Gregor Schoeler dan Johann Fück; dan kelompok ketiga yang
mengambil jalan tengah antara lain Motzki, D. Santillana, G.H.
Juynboll, Fazlur Rahman dan James Robson (Hallaq, 1999).
BAB 6
MODEL KAJIAN ILMU KALAM
Istilah kalam biasanya diterjemahkan sebagai“kata” atau “firman”,
namun kata ini menjadi lebih layak maknanya jika diterjemahkan
“diskusi” atau “argumen” atau “perdebatan”. Mereka yang terlibat dalam
diskusi atau perdebatan disebut sebagai mutakallimun (orang-orang yang
mempraktikan kalam atau perdebatan). Istilah ini memiliki kedudukan
khusus ketika para muhadisun melarang perdebatan semacam ini, karena
kaum Muslim masa awal tidak pernah mengenal dan tak pernah
terlibat dalam perdebatan tersebut. Mereka yang berpartisipasi dalam
perdebatan semacam itu dikatakan berbicara tentang atau
mendiskusikan topik-topik yang terlarang. Para penganjur kalam juga
suka menyebutnya sebagai`ilm al-usul atau `ilm at-tawhid, dan dengan
9
sebutan tersebut banyak topik terus diajarkan dan didiskusikan
dilembaga-lembaga pendidikan Islam hingga saat ini. Kemunculan ilmu
kalam adalah akibat dari banyak kontroversi yang telah memecah
belah komunitas Muslim pada masa-masa awal. Meskipun kemunculan Islam
ditandai dengan polemik dengan kaum musyrik dan pengikut wahyu-wahyu
terdahulu, kontroversi tentang persoalan-persoalan keagamaan
fundamental tidak disukaioleh kaum Muslim awal, khususnya selama masa
hidup Nabi. Namun, perselisihan, utamanya dalam masalah politik, pecah
segera setelah wafatnya Nabi, dan diikuti dengan tragedy yang membawa
pada pembunuhan khalifah Usman pada tahun 656, masa dimana perpecahan
dalam sistem politik terjadisetelah kematian Nabi.
BAB 7
A. Mistisisme: Fenomena Universal
Tasawuf atau dikenal sebagai mistisisme Islam adalah fenomena
universal yang menggambarkan upaya manusia untuk meraih kebenaran.
Tasawuf juga dikenal sebagai pengetahuan intuitif tentang Tuhan atau
Realitas Ultim yang diraih melalui pengalaman keagamaan personal.
Yakni kesadaran akan realitas transenden atau Tuhan melalui
meditasiatau kontemplasi batin. Atau disebut juga sebagai sesuatu yang
memiliki makna tersembunyi atau makna simbolik yang mengilhami
pencarian atas sesuatu yang misteri dan dahsyat. Sedangkan sufi ialah
orang yang berusaha mencapai kesatuan dengan Tuhan melalui kontemplasi
spiritual. Dalam buku Sufism: An Account of the Mystics of Islam, A.
J. Arberry (1950: 11) menyatakan bahwa kaum orientalis dan sejarawan
agama melihat tasawuf dengan cara seragam. Tasawuf dipandang sebagai
fenomena dunia yang permanen dan tunggal. Arberry menegaskan bahwa
pengamatan atas fenomena tasawuf atau mistisisme sebagai tunggal dan
10
serupa, apa pun agama yang dianut oleh seorang sufi mistikus, adalah
suatu pemahaman yang banal. Para sarjana kontemporer berjuang untuk
memahami keragaman dan dinamika yang ada dalam fenomena mistik
sebagaimana termini festasi dalam berbagai tradisi. Mereka berupaya
menelusuri berbagai makna dan ragam kesimpulan tentang tasawuf yang
diambil dari berbagai konteks. Clifford Geertz (1971: 23-24)
menyatakan bahwa penggunaan konsep-konsep tentang tasawuf mistisisme
harus berdasarkan pada studi mengenai keragaman “sebagaimana yang kita
jumpai”, bukan memformulasi generalisasi yang seragam dan definisi
yang berlaku untuk semua. Dengan cara demikian, konsep-konsep sepert
imistisisme dan mistikus, tasawuf dan sufimen jadi sangat kaya dan
berakar. Kita perlu menganalisis hakikat keragaman sebagaimana adanya,
kemudian menelusuri berbagai makna dan konsep-konsep itu. Karena itu
kajian semacam ini setidaknya akan mempelajari fakta-fakta yang ada
dalam keragaman itu. Sementara sarjana lain seperti Rhys Davids yang
ahli dalam kajian Budha, kebingungan dengan kompleksitas dan keragaman
dalam konsep-konsep mistikus atau mistisisme sehingga ia berkesimpulan
bahwa menggunakan istilah-istilah tersebut lebih banyak membingungkan
daripada membantu (Awn, 1983).
BAB 8
MODEL KAJIAN USUL FIKIH DAN FIKIH
A. Definisi dan Ruang Lingkup
Usul fikih dan fikih mempunyai hubungan yang sangat erat. Yang pertama
merupakan akar dari hukum Islam yang membahas indikasi-indikasi dan
metode-metode dimana aturan-aturan fikih dideduksi dari sumber-
sumbernya. Indikasi-indikasi ini dijumpai utamanya dalam Al-Qur’an dan
Sunnah yang merupakan sumber utama syariah. Aturan-aturan fikih
11
berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah yang sejalan dengan sejumlah prinsip
dan metode yang secara kolektif dikenal dengan sebutan usul fikih.
Sebagian sarjana menjelaskan usul fikih sebagai metodologi hukum,
suatu penjelasan yang akurat namun tidak lengkap. Meskipun metode-
metode penafsiran dan deduksi merupakan perhatian utama bagi usul
fikih namun ia bukan semata diperuntukkan pada metodologi. Katakanlah
bahwa usul fikih merupakan ilmu mengenai sumber-sumber dan metodologi
hukum yang akurat dalam arti bahwa Al-Qur’an dan Sunnah merupakan
sumber sekaligus materi bahasan dimana metodologi usul fikih
diterapkan. Al-Qur’an dan Sunnah sendiri mengandung sangat sedikit
metodologi, namun lebih menyediakan inidikasi-indikasi dimana aturan-
aturan syariah dapat dideduksi. Metodologi usul fikih sesungguhnya
merujuk kepada metode-metode penalaran seperti analogi qiyas,
istihsan, istishab, dan aturan-aturan penafsiran dan deduksi. Semua
ini didesain untuk berperan sebagai alat bantu menuju pemahaman yang
benar tentang sumber-sumber dan ijtihad.
BAB 9
MODEL KAJIAN HERMENEUTIKA: Studi Hermeneutika Pembebasan Farid Esack
Sebagai firman Allah swt., Al-Qur’an sesungguhnya merupakan bentuk
nyata campur tangan Tuhan dalam sejarah manusia. Namun, ia tidak
bermakna tanpa campur tangan pikiran dan kesadaran manusia itu
sendiri. Oleh karena itu, cara manusia mendekati Al-Qur’an sangat
berperan dalam menafsir¬kannya dan menghasilkan makna. Sudah banyak
kita jumpai warisan tradisional tafsir Al-Qur’an yang berlimpah dalam
Islam, sebagaimana telah disebut pada bab terdahulu. Sebagai akibat
perkembangan baru kajian Islam didunia dan pengaruh perkembangan ilmu-
ilmu sosial dan humaniora yang semakin canggih pada umumnya, kajian
12
Al-Qur’an semakin membuka diriterhadap pertumbuhan metodologidan
pendekatan kontemporer. Hermeneutika kontemporer, terutama productive
hermeneutics ala Gadamer atau al-Qira’ah al-muntijah menurut Nasr
Hamid Abu Zayd (1994:144), membuka pengakuan terhadap cara baru
pembacaan Al-Qur’an yang menerima fakta adanya prasangka-prasangka
yang sah (Gadamer, 1992: 261). Metode initernyata mengilhami sejumlah
sarjana Muslim untuk melakukan interpretasi terhadap fenomena Al-
Qur’an, dapat disebutkan misalnya Fazlur Rahman, Mohammed Arkoun,
Hassan Hanafidan Farid Esack.
BAB 1 0
MODEL KAJIAN FILSAFAT: Studi Hibrida Filsafat Fondasionalisme dan
Hermeneutika
Pergumulan otoritarianisme, otoritatif dan otoritas didunia Islam,
sebagaimana telah dipaparkan oleh Khaled Abou al- Fadl dalam karyanya
Speaking in the God’s Name, merupakan fakta sejarah yang tak
terelakkan dan mungkin akan terus berjalan. Munculnya fatwa mutakhir
dari MUI mengenai Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan menyesatkan dan
pengharaman atas paham-paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme,
adalah contoh betapa sebuah lembaga keagamaan “otoritatif” telah
menjerumuskan diridalam kubangan “otoritarianisme religius”. Disebut
otoritarianisme karena MUI secara terbuka telah memasuki wilayah hak
prerogatif Tuhan dan mencurinya atas nama kepentingan agama. Belum
dibuka kesempatan dialog secara terbuka dengan berbagai elemen atau
kelompok masyarakat Muslim yang menjadi sasaran fatwa tersebut. Fatwa
MUI dan tertutupnya pintu dialog dikalangan internal Muslim,
memperlihatkan ada upaya-upaya sistematis hegemoni tafsir tertentu
tentang apa, siapa, dan bagaimana Islam. Perlu disadari bahwa tafsir 1
13
bukanlah agama, ia produk akal pikiran sesuai dengan ruang dan waktu
dan tingkat pemahaman intelektual manusia. Meskipun sumbernya adalah
kitab suci dan sunnah, tafsir dapat salah, ia dapat berubah sesuai
dengan semangat zamannya (zeitgeist). Oleh karena itu, tafsir menjadi
asing jika horizon perbendaharaan kata dan rumusannya tak
berdialektika dan bercermin pada perubahan pengalaman kognitif,
kultural dan spiritual. Sebab temuan-temuan ilmiah yang bersifat
empirik, sosial, maupun humaniora berpengaruh besar membentuk
pengalaman keberagamaan manusia, karena keberagamaan bukan wilayah
yang terpisah dari struktur dasar kehidupan. Jika semua itu diabaikan,
pemikiran keagamaan hanya bersifat reaktif, bukan diskursif dan makin
jauh dari kenyataan empirik (Dewey, 1960: 161-186).
BAB 1 1
MODEL KAJIAN PENDIDIKAN: Pendekatan Multikultural terhadap Pendidikan
Agama
Kekayaan akan keane karagaman Nusantara agama, etnik, dan budaya
ibarat pisau bermata dua. Disatu sisi, kekayaan ini merupakan khazanah
yang patut dipelihara dan memberikan nuansa dan dinamika bagi bangsa.
Disisi lain, ia dapat pula merupakan titik pangkal perselisihan,
konflik vertikal dan horizontal. Krisis multi dimensi yang berawal
sejak pertengahan 1997 dan ditandai dengan kehancuran perekonomian
nasional, sulit dijelaskan secara mono-kausal. Faktor-faktor yang
terlibat terlalu kompleks dan saling terkait: ada faktor kepentingan
internasional dan kepentingan nasional, sejarah kolonial, sumber daya
alam yang tersedia, keragaman etnik, iklim, agama-agama, tradisi, dan
globalisasi. Cukup banyak konflik komunal terjadi sepanjang krisis,
dan diperparah konflik elite politik yang membuang-buang waktu dan
14
mengarahkan Negara pada perang sipil (Bamualim dkk, ed., 2002).
Sebuah permulaan yang sangat buruk bagi bangsa Indonesia dalam
menyambut abad 21. Krisis moneter dan politik yang berlarut-larut
bergerak dalam suatu proses interrelasi yang sangat kompleks telah
menghasilkan kekacauan yang sulit diprediksi. Berbagai ragam kekerasan
bersilang sengkarut dengan proses demokratisasi yang mandul dan
kebebasan tanpa kesadaran dan penerapan hukum yang berwibawa.
Sementara itu, economic recovery berjalan lambat karena teorientasi
ekonomi pasca era konglomerat masih terbuka untuk dipersoalkan; karena
aparat negara yang berkuasa gagal ketika monopolike kuasaan
terdesentralisir melalui kebijakan otonomisasi daerah yang berjalan
tanpa skenario yang jelas. Tiga rangkaian Undang-undang otonomi daerah
dan penanggulangan korupsi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, serta UU No.28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN masih mengandung
banyak celah untuk korupsi. Semua bentuk korupsi diatas disebabkan
oleh penyalah gunaan kekuasaan untuk meraih keuntungan pribadiyang
berhubungan dengan merembesnya insentif, minimnya informasi dan
transparansi kepada publik, dan kurangnya akuntabilitas publik.
KELEBIHAN
1. Di buat oleh orang hebat, berpendidikan dan berpengalaman luas.
2. Penjelasan tentang bab-babnya sangat rinci dan jelas.
3. Jika tidak mau membeli bukunya , tapi ingin membaca
karyanya(pengertian dan metodelogi studi islam) dapat di download
di iainsalatiga.academia.edu/zakiyuddinbaidhawy
4. Bab-babnya sangat lengkap sesuia pembahasan.
15