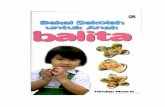BUKU Judul Buku : Penelitian Fenomenologis: Jalan Memaha
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of BUKU Judul Buku : Penelitian Fenomenologis: Jalan Memaha
LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: BUKU
Judul Buku : Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup
Penulis Buku : Yohanis Franz La Kahija
Jumlah Penulis : 1 orang
Status Pengusul : Penulis Tunggal
Identitas Buku : a. ISBN : 978-979-21-5409-2
b. Edisi : Pertama
c. Tahun Terbit : 2017
d. Penerbit : PT Kanisius
e. Jumlah Halaman : 262 halaman
Kategori Buku : Referensi
(beri pada kategori yang tepat) Monograf
Hasil Penilaian Peer Review :
Komponen yang Dinilai Nilai Nilai
rata-rata Reviewer 1 Reviewer 2
a. Kelengkapan Unsur Isi Buku (20%) 7 8 7,5
b. Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan (30%) 9,5 12 10,75
c. Kecukupan dan Kemutahiran Data/Informasi dan
Metodologi (30%) 9,5 12 10,75
d. Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit (20%) 7 8 7,5
TOTAL = (100%) 33 40 36,5
Semarang, 21 April 2021
Peer Review I Prof. Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si., Ph.D.
NIP. 197809012002122001
....................................................
Peer Review II Anggun Resdasari P, S.Psi., M.Psi.
NIP. 198305252009122006
....................................................
LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: BUKU
Judul Buku : Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup Penulis Buku : Yohanis Franz La Kahija
Jumlah Penulis : 1 orang
Status Pengusul : Penulis Tunggal Identitas Buku : a. ISBN : 978-979-21-5409-2
b. Edisi : Pertama
c. Tahun Terbit : 2017
d. Penerbit : PT Kanisius
e. Jumlah Halaman : 262 halaman
Kategori Buku : Referensi (beri pada kategori yang tepat) Monograf
Hasil Penilaian Peer Review :
Komponen
Yang Dinilai
Nilai Maksimal Buku
Nilai yang Diperoleh Referensi
Monograf
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%) 8 7
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)
12 9,5
c. Kecukupan dan kemutahiran
data/informasi dan metodologi
(30%)
12 9,5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas
penerbit (20%)
8 7
Total = (100%) 40 33
Nilai yang Diperoleh= (100% x 33) = 33
Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer:
1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Unsur-unsur buku ini terdiri dari cover, kata pengantar, renungan sebelum membaca, daftar isi, daftar tabel, 13 bab yang masing-masing secara mendalam membahas tentang penelitian fenomenologis
sebagai suatu metode dalam memahami pengalaman hidup, glosarium, daftar pustaka, lampiran, dan
biografi penulis. Unsur – unsur ini telah memenuhi unsur-unsur yang seharusnya dimiliki buku
referensi.
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Buku referensi ini mencakup 13 bab yang berisi tentang pendekatan fenomenologis dalam penelitian kualitatif, penelitian dan peneliti fenomenologis, interpretative phenomenological analysis, penelitian
fenomenologis deskripstif,
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi:
Informasi yang disampaikan dalam buku ini tergolong mutakhir, meliputi artikel jurnal dan buku.
Meskipun demikian, referensi yang merupakan terbitan 10 tahun terakhir kurang dari 80%.
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:
Buku referensi ini diterbitkan oleh PT Kanisius dengan kualitas cukup memadai dan memiliki ISBN.
Hasil cetak buku cukup jelas yang terlihat dari huruf dan warnanya.
5. Indikasi plagiasi:
Hasil turnitin similarity indeks =12%, yang menunjukkan orisinalitas buku referensi ini memadai dan
tidak menunjukkan adanya indikasi plagiasi.
40
6. Kesesuaian bidang ilmu:
Buku referensi ini mengulas tentang penelitian fenomenologis yang sejalan dengan bidang ilmu
pengusul yaitu psikologi.
Semarang, 17 April 2021
Reviewer 1,
Prof. Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si., Ph.D. NIP. 197809012002122001
Jabatan (Gol): Guru Besar (IVa)
Unit kerja: Fakultas Psikologi UNDIP
Bidang ilmu: Psikologi
LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: BUKU
Judul Buku : Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup
Penulis Buku : Yohanis Franz La Kahija
Jumlah Penulis : 1 orang
Status Pengusul : Penulis Tunggal
Identitas Buku : a. ISBN : 978-979-21-5409-2
b. Edisi : Pertama
c. Tahun Terbit : 2017
d. Penerbit : PT Kanisius
e. Jumlah Halaman : 262 halaman
Kategori Buku : Referensi
(beri pada kategori yang tepat) Monograf
Hasil Penilaian Peer Review :
Komponen
Yang Dinilai
Nilai Maksimal Buku
Nilai yang Diperoleh Referensi
Monograf
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%) 8 8
b. Ruang lingkup dan kedalaman
pembahasan (30%)
12 12
c. Kecukupan dan kemutahiran
data/informasi dan metodologi
(30%)
12 12
d. Kelengkapan unsur dan kualitas
penerbit (20%)
8 8
Total = (100%) 40 40
Nilai yang Diperoleh= (100%x40)= 40
Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer:
1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Buku referensi ini sudah ditulis sangat lengkap dan sesuai seperti persyaratan buku referensi mulai dari
teori hingga penerapannya dalam penelitian, terutama tentang penelitian kualitatif khususnya tentang
metode fenomenologis.
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Pembahasan sangat mendalam dan lengkap untuk menjelaskan penelitian kualitatif dengan menggunakan
metode fenomenologis mulai dari landasan teori, persiapan di lapangan/ pengumpulan data hingga
analisis. Sehingga buku ini bisa digunakan sebagai referensi untuk perkuliahan pada mahasiswa S1
hingga S3 tentang metode penelitian fenomenologis.
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi:
Buku ini sudah sesuai, sangat lengkap dan terarah baik untuk penjelasan serta metodologinya sehingga
bisa digunakan panduan untuk mata kuliah seminar proposal, skripsi. Buku ini juga telah didukung
dengan data/informasi yang komprehensif baik secara teoritis maupun contoh-contoh dalam analisa
dengan menggunakan secara metodologis.
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:
Unsur kualitas buku sudah cukup baik, yaitu diterbitkan oleh PT. Kanisius. ., yang telah diakui secara
nasional sebagai kualitas penerbit yang cukup baik. sehingga kualitas penerbit dari buku ini sudah
memenuhi kelengkapan PAK yang diminta.
40
5. Indikasi plagiasi:
Buku ini tidak memenuhi unsur plagiasi, karena dengan hasil cek turnitin, sudah memenuhi standar non-
plagiasi dan memiliki orisinalitas sebagai buku.
6. Kesesuaian bidang ilmu:
Buku yang disusun ini sangat sesuai dengan rekam jejak keilmuan dan penelitian dari penulis yaitu
khususnya tentang metode penelitian psikologi. Buku ini bisa digunakan untuk menambah pengetahuan
tentang metode fenomenologis sebagai salah satu metode penelitian dalam kualiatif, sehingga bisa
digunakan baik oleh mahasiswa psikologi, praktisi psikolog, peneliti maupun dosen di bidang psikologi
yang tertarik menggunakan metode tersebut.
Semarang, 31 Desember 2020
Reviewer 2
Anggun Resdasari P, S.Psi., M.Psi, Psikolog
NIP. 198305252009122006
Jabatan (Gol): Lektor (IIIc)
Unit kerja: Fakultas Psikologi UNDIP
Bidang ilmu: Psikologi
Penelitian Fenomenologis Jalan Memahami Pengalaman Hidup1017002152© 2017 PT Kanisius
PENERBIT PT KANISIUS (Anggota IKAPI)Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, SlemanDaerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIATelepon (0274) 588783, Fax (0274) 563349E-mail : [email protected] : www.kanisiusmedia.co.id
Cetakan ke- 5 4 3 2 1
Tahun 21 20 19 18 17
Pengarang : YF La KahijaEditor : Ganjar SudibyoDesainer Isi : Kartika DewiDesainer Cover : Hermanus Yudi
ISBN 978-979-21-5409-2
Hak cipta dilindungi undang-undang.Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Dicetak oleh PT Kanisius Yogyakarta
Wir wollen auf die ‘Sachen selbst’ zurückgehen.
Kami ingin kembali ke “fakta-fakta itu sendiri (pengalaman langsung)"
Edmund Husserl (Peletak dasar Fenomenologi)
t
Revenir aux choses mêmes, c’est revenir à ce monde avant la connaissance …
Kembali ke fakta-fakta itu sendiri (pengalaman langsung) berarti kembali pada dunia sebelum munculnya pengetahuan (teori) …
Maurice Merleau-Ponty (Filsuf fenomenologi Prancis)
vii
Pengantar
Buku Penelitian Fenomenologis ini hadir sebagai respons terhadap kekosongan literatur tentang pendekatan fenomenologis yang tersedia dalam bahasa Indonesia. Keterbatasan itu telah menggelembungkan banyak pertanyaan tentang apa itu penelitian fenomenologis dan bagaimana menjalankan penelitian fenomenologis. Ada dua pengalaman pribadi yang telah memicu penulisan buku ini. Pengalaman yang pertama adalah pengalaman berkumpul dengan mahasiswa dan bertanyajawab tentang penelitian fenomenologis. Pertanyan-pertanyaan praktis yang mereka ajukan membantu saya memetakan kebutuhan peneliti-peneliti fenomenologis di tengah kekosongan literatur. Pengalaman yang kedua adalah pengalaman mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih teoretis dan konseptual dari teman-teman sejawat yang berprofesi sebagai dosen.
Fenomenologi dalam Riset
Ada cukup banyak pendekatan yang berkembang dalam penelitian kuali tatif. Di antara beragam pendekatan itu, pendekatan fenomenologis adalah pendekatan yang paling akrab dengan psikologi. Secara historis, masa kemunculan psikologi modern adalah masa kemunculan filsafat fenomenologis (fenomenologi). Pada bulan Desember 1879, Wilhelm Wundt (1832-1920), yang dinobatkan sebagai “Bapak psikologi modern” , mendirikan laboratorium psikologi di Universitas Leipzig. Wundt hidup sejaman dengan Franz Brentano (1837-1917), inspirator fenomenologi. Salah satu murid Brentano, Carl Stumpf, mendirikan institut psikologi di
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidupviii
Berlin pada tahun 1900 dan menjabat sebagai direktur laboratorium. Dari institut psikologi inilah, lahir tokoh-tokoh penting dalam psikologi Gestalt. Selain itu, Carl Stumpf adalah pembimbing disertasi Edmund Husserl, ahli matematika yang kemudian dikenal sebagai Bapak fenomenologi.
Dalam perkembangan selanjutnya, fenomenologi diterapkan sebagai pen-dekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan memahami pengalaman hidup dari orang yang mengalami langsung suatu peristiwa (fenomena). Penerapan awal dilakukan pada tahun 1970-an oleh Amedeo Giorgi, pakar di bidang psikologi eksperimental, yang kemudian dikenal sebagai peletak dasar penelitan fenomenologis deskriptif. Penerapan selanjutnya dilakukan pada tahun 1990-an oleh Jonathan A. Smith, pakar di bidang psikologi kesehatan, yang meletakkan fondasi penelitian fenomenologis interpretatif yang lebih umum dikenal dengan istilah “interpretative phenomenological analysis (IPA)”. Dua versi pendekatan fenomenologis ini banyak digunakan saat ini.
Dalam buku ini, pembaca akan menemukan bahwa dua versi penelitian fenomenologis itu (fenomenologis deskriptif dan IPA) tidak bisa dilepaskan dari gejolak dalam filsafat fenomenologis (fenomenologi). Ada dua filsuf besar dalam fenomenologi yang memiliki perspektif yang berbeda dalam memahami pengalaman manusia, yaitu Edmund Husserl yang menekankan deskripsi pengalaman dan Martin Heidegger yang menekankan interpretasi atau penafsiran pengalaman. Dua versi penelitian fenomenologis itu akan menjadi jelas saat kita membaca buku ini secara bertahap dari bab ke bab. Oleh karena itu, saya menyarankan pembaca untuk mengikuti alur bab demi bab.
Ada tren yang sedikit mengejutkan belakangan ini, yaitu penelitian fenomenologis telah berkembang melampaui psikologi. Beberapa disiplin lain di luar psikologi juga bisa merasakan manfaatnya. Belum lama berselang, saya dihubungi secara terpisah oleh dua mahasiswa akuntansi yang tertarik menggunakan penelitian fenomenologis untuk memahami pengalaman pribadi akuntan terkait dengan pelaksanaan kebijakan tertentu. Tampaknya, penelitian fenomenologis menarik untuk digunakan secara interdisipliner atau lintas-keilmuan. Sejauh ini bidang-bidang yang bisa dideteksi menggunakan pendekatan fenomenologis adalah keperawatan, kedokteran, komunikasi, kepustakaan, pendidikan, dan arsitektur. Perluasan manfaat dari
Pengantar ix
penelitian fenomenologis seperti itu bisa dimengerti karena fenomenologi memang terkait dengan pengalaman manusia. Di mana ada orang yang mengalami, di situ penelitian fenomenologis bisa digunakan.
Tentang Isi Buku
Buku ini berisi 14 bab yang dirancang untuk membawa pembaca sampai pada kemampuan menjalankan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Dalam Bab I, saya membicarakan penelitian kualitatif secara umum untuk memperlihatkan kekhasan penelitian fenomenologis di antara beberapa pendekatan yang berkembang dalam penelitain kualitatif. Dengan demikian, Bab I sebenarnya hanyalah latar belakang untuk materi pokok yang ingin disampaikan buku ini. Mulai dari Bab II dan seterusnya, kita berfokus hanya pada penelitian fenomenologis.
Dalam Bab II, kita membentuk pemahaman dasar tentang apa itu fenomenologi (filsafat fenomenologis), apa itu fenomena, dan apa itu penelitian fenomenologis. Ketiganya saling terkait dan menjadi fondasi untuk membentuk pemahaman yang lebih jauh tentang penelitian fenomenologis. Selanjutnya dalam Bab III dan Bab IV, kita mendapat gambaran umum tentang dua versi penelitian fenomenologis, yaitu penelitian fenomenologis deskriptif dan interpretative phenomenological analysis (IPA). Di situ, kita mencoba melihat kekhasan masing-masing versi pendekatan fenomenologis, termasuk cara merumuskan judul penelitian. Dari Bab V sampai Bab XI, kita bertemu dengan langkah-langkah menjalankan penelitian fenomenologis, mulai dari persiapan ke lapangan, pengumpulan data saat di lapangan, dan analisis data setelah dari lapangan. Dalam Bab XII, kita bisa membaca salah satu format penyusunan laporan yang boleh digunakan jika dipandang perlu karena setiap fakultas biasanya memiliki formatnya sendiri. Tidak lupa, penulis juga menampilkan topik tentang “penelitian eksistensial-fenomenologis” di Bab XIII untuk menunjukkan kedekatan antara fenomenologi (filsafat fenomenologis) dan eksistensialisme (filsafat eksistensial). Akhirnya, buku ini ditutup dengan Bab XIV yang berisi pertanyaan dan jawaban yang cukup sering muncul saat saya bertanya-jawab dengan mahasiswa. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin saja terkoneksi dengan pertanyaan yang ada di benak pembaca.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidupx
Syukur dan Terima Kasih
Akhirnya, saya ingin mengekspresikan rasa syukur dengan berterima kasih pada pihak-pihak yang telah menyemangati penyelesaian buku ini. Terima kasih untuk seluruh staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro yang telah mengizinkan penggunaan penelitian fenomenologis untuk mahasiswa. Saya percaya, sikap terbuka yang selama ini dikembangkan adalah jalan membuka pintu-pintu kebenaran. Terima kasih yang dalam untuk dorongan semangat dari Prof. Drs. Subandi, Ph.D yang sudah lebih dahulu menerapkan penelitian fenomenologis di Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Thomas Hidya Tjaya, pengajar fenomenologi dan eksistensialisme di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara yang sudah menyediakan waktu membaca naskah buku ini, dan Dr. Zainal Abidin dari Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran yang juga menyemangati publikasi buku ini.
Rasa terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada semua mahasiswa yang bersemangat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Semoga buku ini bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering diajukan. Akhirnya, terima kasih untuk Penerbit Kanisius yang telah membolehkan buku ini mengalir ke publik. Terima kasih Mas Ganjar Sudibyo, editor yang dengan pengalamannya menjalankan riset fenomenologis telah memeriksa buku ini dengan serius sambil menyodorkan catatan-catatan kritisnya, dan semua tim yang terlibat dalam pemolesan akhir buku ini.
Semoga buku kita ini bisa memberi manfaat bagi khazanah penelitian kualitatif di Indonesia.
Semarang, 20 September 2017
YF La Kahija
xi
Renungan Sebelum Membaca
Setiap hal penting yang saya ketahui tentang manusia, yang saya pelajari dari mereka, adalah mendengarkan mereka, mencoba ikut merasakan hidup mereka dari dalam, tanpa mengadili atau menilai mereka, hanya mencoba ikut merasakan setepat mungkin, bagaimana sebenarnya pribadi ini menghayati hidupnya saat ini.
Carl Rogers — peletak dasar psikologi dan terapi humanistik
Janganlah pernah lupa bahwa dalam psikologi, sarana yang Anda gunakan untuk menilai dan mengamati psike [jiwa] adalah psike [jiwa] itu sendiri. Pernahkah Anda melihat martil yang menghantam dirinya sendiri? [Itulah yang terjadi dalam psikologi] Dalam psikologi, pengamat sekaligus juga yang diamati [jiwa pengamat bertemu dengan jiwa yang diamati]. Psike [jiwa] bukan hanya objek, tetapi juga subjek dari ilmu pengetahuan kita [psikologi kita]. Jadi Anda lihat, psikologi adalah lingkaran setan dan kita harus menjadi sangat rendah hati. Hal terbaik yang bisa kita harapkan dari psikologi adalah setiap orang meletakkan kartu-kartunya di meja dan mengakui, “Saya melihat segala sesuatu begini dan begitu dan seperti inilah cara saya melihatnya.” Barulah kemudian kita bisa membandingkan catatan-catatan …. Sejauh kita mengakui pandangan-pandangan pribadi kita [yang subjektif itu], kita benar-benar memberi kontribusi bagi munculnya psikologi yang objektif.
Carl Gustav Jung— psikiater dan psikolog ketidaksadaran *Keterangan dalam kurung kotak dari penulis.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidupxii
Seorang profesor datang menemui Guru Nan-in untuk belajar tentang ajaran spiritual Zen. Mereka duduk bersila berhadap-hadapan. Sang profe sor kemudian bercerita banyak tentang apa saja yang sudah ia baca dan ketahui tentang Zen. Saat sang profesor asyik bercerita, Nan-in menuang teh ke dalam cangkir profesor yang sebelumnya sudah berisi penuh. Dia menuang dan terus saja menuang sampai air teh di cangkir itu luber dan membasahi lantai. Melihat keanehan itu, sang profesor berhenti bercerita dan mengatakan, “Maaf, cangkirnya sudah penuh dan tidak bisa lagi diisi.” Nan-in lalu mengatakan, “Seperti cangkir ini, kamu sudah penuh dengan pikiran dan macam-macam penilaian. Bagaimana aku bisa mengajarimu Zen kalau kamu tidak mengosongkan cangkirmu?”
Kisah Zen
xiii
Daftar Isi
Pengantar ........................................................................................................................................................................................................................... vii
Renungan Sebelum Membaca .................................................................................................................................................. xi
Daftar Isi ............................................................................................................................................................................................................................. xiii
Daftar Kotak ............................................................................................................................................................................................................... xviii
BAB I Pendekatan Fenomenologis dalam Penelitian Kualitatif .......................... 1A. Penelitian Naratif-biografis ....................................................................................................................... 4B. Penelitian Grounded Theory ...................................................................................................................... 6C. Studi Kasus ............................................................................................................................................................................. 11D. Penelitian Etnografis .............................................................................................................................................. 15E. Penelitian Fenomenologis ............................................................................................................................ 17F. Definisi Populer untuk Fenomenologi ................................................................................ 21G. Kemunculan Penelitian Fenomenologis .............................................................................. 26
BAB II Penelitian dan Peneliti Fenomenologis ..................................................................................... 31A. Tentang Fenomenologi ..................................................................................................................................... 31B. Tentang Fenomena ................................................................................................................................................... 36C. Kualitas Peneliti Fenomenologis ...................................................................................................... 39
BAB III Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): Pengantar Singkat dan Formulasi Judul .................................................................................... 45A. Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) .......................................................... 45B. Tiga Pilar IPA .................................................................................................................................................................... 47
1. Fenomenologi .................................................................................................................................................. 472. Hermeneutika .................................................................................................................................................. 493. Idiografi ....................................................................................................................................................................... 51
C. Formulasi Judul dalam IPA ...................................................................................................................... 52
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidupxiv
BAB IV Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Pengantar Singkat dan Formulasi Judul ...................................................................................... 59A. Epochē sebagai Pilar PFD ................................................................................................................................ 64B. Double Descriptive (Deskripsi Ganda) ..................................................................................... 65C. Formulasi Judul dalam PFD ..................................................................................................................... 66
BAB V Persiapan ke Lapangan: Literatur dan Pengumpulan Data ................ 73A. Bacaan Literatur dan Sikap Peneliti .......................................................................................... 75B. Wawancara Semi-terstruktur dan Panduan Wawancara ...................... 79C. Panduan Wawancara dalam IPA ........................................................................................................ 80D. Panduan Wawancara dalam PFD .................................................................................................... 86E. Jumlah Partisipan dalam IPA .................................................................................................................. 89F. Jumlah partisipan dalam PFD ............................................................................................................. 92
BAB VI Persiapan ke Lapangan: Menjelang Wawancara ..................................................... 95A. Wawancara yang Eksploratif ..................................................................................................................... 95B. Frekuensi Wawancara dalam IPA dan PFD .................................................................. 99
BAB VII Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): Analisis Data ..................................................................................................................................................................................... 103A. Epochē yang Dinamis ........................................................................................................................................... 107B. Penyajian Transkrip Wawancara ....................................................................................................... 108C. Analisis Transkrip ........................................................................................................................................................ 110 Tahap Analisis 1 dan 2: Penghayatan Transkrip
dan Pencatatan Awal ............................................................................................................................................. 112
BAB VIII Interpretative Phenomenologial Analisis (IPA): Analisis Data Lanjutan ................................................................................................................................................. 117A. Tahap Analisis 3: Perumusan Tema Emergen ......................................................... 118B. Tahap Analisis 4: Perumusan Tema Superordinat ............................................. 123C. Tahap Analisis 5: Pola-pola Antarkasus/Antarpengalaman
Partisipan ................................................................................................................................................................................... 128D. Penataan Seluruh Tema Superordinat .................................................................................... 128E. Melaporkan Hasil Analisis .......................................................................................................................... 134F. Pembahasan ........................................................................................................................................................................... 138
BAB IX Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Konsep-konsep Filosofis ............................................................................................................................................. 139A. Dua Raksasa Fenomenologis,
Dua Pendekatan Fenomenologis ...................................................................................................... 139B. Konsep-konsep Filosofis PFD ................................................................................................................ 143
Daftar Isi xv
1. Semboyan Fenomenologis ........................................................................................................ 1442. Pengalaman Langsung (Lived Experience) ....................................................... 1453. Sikap Natural versus Sikap Fenomenologis ................................................. 1474. Reduksi Fenomenologis ................................................................................................................. 1485. Variasi Imajinatif (Imaginative Variation) ........................................................ 1496. Konstitusi dan Konstituen ........................................................................................................ 151
BAB X Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Analisis Data ........... 155A. Amedeo Giorgi dan Fenomenologi Deskriptif ..................................................... 159B. Prosedur Analisis Data ala Giorgi ................................................................................................... 161C. Prosedur Analisis Data ala Moustakas .................................................................................. 166
BAB XI Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Descriptive Phenomenological Analysis (DPA) ......................................................................................................... 175A. Membedakan Analisis PFD dari IPA ...................................................................................... 175B. Descriptive Phenomenological Analysis (DPA) ............................................................ 176C. Alur Analisis data dalam DPA ............................................................................................................. 177D. Sekilas tentang Esensi dan Intuisi ................................................................................................. 186
BAB XII Penyusunan Laporan Penelitian ....................................................................................................... 189A. Judul Penelitian .............................................................................................................................................................. 190B. Membuat Judul yang Berdaya Tarik ......................................................................................... 191C. Penulisan Abstrak ....................................................................................................................................................... 195D. Latar Belakang (Introduction/Background) ....................................................................... 196E. Metode (Method) ......................................................................................................................................................... 197F. Hasil Analisis Data ................................................................................................................................................... 203G. Pembahasan (Discussion) ................................................................................................................................ 203H. Kesimpulan ............................................................................................................................................................................ 204I. Format Susunan Laporan Penelitian ........................................................................................ 205
BAB XIII Penelitian Eksistensial-fenomenologis? ............................................................................ 209A. Filsafat Eksistensial (Eksistensialisme) .................................................................................... 211B. Istilah “Eksistensial-fenomenologis” ........................................................................................... 213
BAB XIV Pertanyaan-pertanyaan Frekuen .................................................................................................... 221
Glosarium ......................................................................................................................................................................................................................... 233
Daftar Pustaka ........................................................................................................................................................................................................ 245
Lampiran Kotak Berwarna ............................................................................................................................................................ 249
Tentang Penulis ..................................................................................................................................................................................................... 262
xvii
Daftar Kotak
Kotak 1.1 Pertanyaan Penelitian dan Pendekatan ..................................................................................... 2Kotak 1.2 Definisi Populer untuk Fenomenologi ....................................................................................... 21Kotak 1.3 Penelusuran Online untuk Judul The Lived Experience ..................................... 24Kotak 1.4 Bab Buku Husserl tentang Hubungan Psikologi
dan Fenomenologi ....................................................................................................................................................... 26Kotak 2.1 Definisi Fenomenologi ......................................................................................................................................... 32Kotak 2.2 Definisi Penelitian Fenomenologis .................................................................................................. 35Kotak 3.1 Contoh-contoh Formulasi Judul dalam Penelitian IPA ............................... 53Kotak 4.1 Penelusuran Online Judul PFD .............................................................................................................. 68Kotak 4.2 Contoh-contoh Formulasi Judul dalam PFD ................................................................ 69Kotak 5.1 Pemeriksaan Pemahaman Fenomenologis
Sebelum Pengumpulan Data ..................................................................................................................... 74Kotak 5.2 Pertanyaan-pertanyaan untuk Menggali Pengalaman ..................................... 80Kotak 5.3 Pertanyaan-pertanyaan yang Perlu Dihindari ................................................................ 82Kotak 5.4 Contoh-contoh Panduan Wawancara ......................................................................................... 83Kotak 7.1 Transkrip Orisinal dan Pencatatan Awal ............................................................................... 113Kotak 8.1 Alur Analisis Data ....................................................................................................................................................... 118Kotak 8.2 Pengembangan Tema Emergen ............................................................................................................. 120Kotak 8.3 Sebaran Awal Tema Emergen .................................................................................................................. 124Kotak 8.4 Pengelompokan Tema ........................................................................................................................................... 125Kotak 8.5 Pengembangan Tema Superordinat ................................................................................................ 126Kotak 8.6 Poin-poin Penting dalam Pengembangan Tema Emergen
dan Tema Superordinat ....................................................................................................................................... 127Kotak 8.7 Tabel Induk untuk Tema Semua Partisipan ..................................................................... 130Kotak 8.8 Tabel Identifikasi Tema Berulang ...................................................................................................... 133Kotak 9.1 Hubungan noesis-noema ...................................................................................................................................... 151
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidupxviii
Kotak 10.1 Perbandingan Tiga Alur Analisis PFD .................................................................................... 173Kotak 11.1 Penghayatan Transkrip dan Pembentukan Unit Makna .............................. 179Kotak 11.2 Deskripsi untuk Unit Makna .................................................................................................................... 180Kotak 11.3 Deskripsi Psikologis untuk Deskripsi Unit Makna .............................................. 181Kotak 11.4 Deskripsi Struktural dan Deskripsi Psikologis ............................................................ 182Kotak 11.5 Mentransformasikan Deskripsi Struktural Menjadi Tema ...................... 183Kotak 11.6 Contoh Tabel Penyajian Tema Partisipan ............................................................................ 184Kotak 11.7 Contoh Tabel Penyajian Sintesis Tema .................................................................................... 185Kotak 12.1 Perbandingan Formulasi Judul IPA dan PFD .............................................................. 191Kotak 12.2 Contoh Abstrak dan Bagian-bagiannya .................................................................................. 196Kotak 12.3 Pengecekan Isi Latar Belakang .............................................................................................................. 197Kotak 12.4 Validitas (Kualitas Penelitian) dalam Penelitan Fenomenologis ..... 201Kotak 12.5 Pengecekan Isi Pembahasan ........................................................................................................................ 204Kotak 12.6 Pengecekan Isi Kesimpulan .......................................................................................................................... 205Kotak 13.1 Penelusuran Online Judul Penelitian Eksistensial-Fenomenologis ...... 209
1
BAB I
Pendekatan Fenomenologis dalam Penelitian Kualitatif
Banyaknya kajian kualitatif yang bermunculan saat ini memperlihatkan semakin jelas bahwa pendekatan dalam penelitian kualitatif itu beragam. Kebanyakan ini menyebabkan pernyataan seperti, “Saya ingin melakukan penelitian kualitatif ” sudah tidak lagi cukup. Kita perlu memperjelas pen-dekatan kualitatif yang kita pilih dan alasan yang mendasari pilihan kita itu.
Dalam beberapa buku metodologi penelitian kualitatif, biasanya ada beberapa pendekatan kualitatif yang ditawarkan. Berikut ini beberapa pendekatan yang umum ditemui dalam psikologi dan ilmu-ilmu kemanusiaan yang lain:
• pendekatan naratif-biografis,• pendekatan grounded theory,• pendekatan studi kasus,• pendekatan analisis diskursus, • pendekatan etnografis,• pendekatan fenomenologis.
Daftar itu masih bisa diperpanjang bila kita ingin menampung semua pendekatan yang ada dalam buku-buku metodologi penelitian kualitatif. Meskipun buku ini tentang penelitian fenomenologis, ada baiknya bila kita juga mengenal sekilas tentang pendekatan-pendekatan lain yang berkembang dalam penelitian kualitatif. Pengetahuan tentang keberagaman pendekatan
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup2
dalam penelitian kualitatif akan membuat kita semakin memahami kekhasan pendekatan fenomenologis.
Pendekatan penelitian yang kita pilih sangat tergantung pada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu sendiri bermula dari keingintahuan atau keinginpahaman. Dalam bahasa Jawa, keingintahuan atau keinginpahaman yang mendasari penelitian itu disebut gumun; sementara dalam bahasa Inggris disebut wonder. Gumun atau wonder itu adalah kombinasi dari rasa penasaran, rasa heran, rasa ingin tahu, rasa ingin kejelasan. Dalam penelitian ilmiah, gumun/wonder itu ditunjukkan lewat pertanyaan penelitian (research question) yang diajukan. Nah, pertanyaan penelitian inilah yang akan menentukan pendekatan kualitatif apa yang cocok atau sesuai bagi peneliti.
Kotak 1.1 memperlihatkan bagaimana pertanyaan penelitian terhubung dengan pendekatan kualitatif yang digunakan. Anggap saja kita bertemu dengan satu kejadian/peristiwa yang membuat kita gumun/wonder. Kejadian itu adalah “Saya menyaksikan/mendengar/membaca orang yang melukai diri sendiri saat stres.”
Kotak 1.1 Pertanyaan Penelitian dan Pendekatan
Pertanyaan Penelitian Tujuan Peneliti Pendekatan
Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi dan menentukan tindakan melukai diri sendiri saat stres?
Peneliti ingin bisa memberi penjelasan pada level teoretis mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tindakan melukai diri sendiri saat stres.
Grounded theory
Bagaimana orang yang melukai diri sendiri saat stres memaknai tindakannya itu?
Peneliti ingin memahami bagaimana orang memaknai pengalamannya melukai diri sendiri saat stres.
Fenomenologis
Bagaimana kisah atau perjalanan hidup seseorang membuat dia melukai diri sendiri saat stres?
Peneliti ingin memahami bagaimana kisah hidup seseorang punya kaitan dengan tindakannya melukai diri sendiri saat stres.
Naratif-biografis
BAB I Pendekatan Fenomenologis dalam Penelitian Kualitatif 3
Sampai di sini, kita sudah berkali-kali menemui istilah “pendekatan” dalam penelitian kualitatif. Mengapa tidak menggunakan istilah “rancangan (desain)” atau “tipe” dalam penelitian kualitatif ? Semakin banyak buku metodologi penelitian kualitatif yang Anda baca, semakin bervariasi istilah yang Anda temui. Masing-masing istilah itu tentu saja punya alasan di baliknya.
• Bagi yang menyukai istilah “rancangan/desain (design)”, macam-macam penelitian kualitatif dilihat sebagai macam-macam ran-cangan yang bisa Anda tunjuk atau pilih sebagai pola dasar dalam mengumpulkan dan memproses data yang didapatkan dari partisipan. Kata Latin designare yang berarti menunjuk atau memilih.
• Bagi yang menyukai istilah “tipe”, macam-macam penelitiankualitatif dilihat sebagai macam-macam bentuk atau jenis dalam mengumpulkan dan memproses data yang didapatkan dari partisipan. Kata Latin typus berarti jenis atau bentuk.
Dalam buku ini, saya menggunakan istilah “pendekatan (approach)” kualitatif karena macam-macam penelitian kualitatif menunjukkan strategi yang berbeda baik dalam mendekati partisipan/subjek di lapangan maupun dalam menganalisis data/informasi yang didapatkan di lapangan.
Ada cukup banyak pendekatan yang berkembang dalam penelitian kualitatif. Di antara beragam pendekatan itu, ada beberapa pendekatan yang populer atau umum digunakan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: Bagaimanakah kita bisa mengetahui pendekatan-pendekatan yang populer itu? Populer itu relatif, sangat tergantung pada berapa banyak akademisi yang menggunakannya. Dalam bahasa Latin, populus yang berarti “banyak orang” yang kemudian menjadi people dalam bahasa Inggris. Populer berarti disukai atau diikuti banyak orang. Sebagai ilmuwan, kita boleh mengikuti yang populer, tetapi tidak mengandalkan yang populer. Bisa saja suatu pendekatan yang tadinya tidak populer kemudian menjadi populer. Sebaliknya, pendekatan yang tadinya populer menjadi tidak populer.
Untuk mengetahui pendekatan kualitatif yang populer dalam psikologi, saya kira, buku John W. Creswell (2007) yang berjudul “Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches (Kajian Kualitatif dan Rancangan Penelitian: Memilih di antara Lima Pendekatan)” masih bisa
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup4
dijadikan acuan. Dalam buku itu, kita bisa membaca lima pendekatan dalam penelitian kualitatif psikologis, yaitu (1) studi naratif-biografis, (2) grounded theory, (3) studi kasus, (4) studi etnografis, dan (5) studi fenomenologis.
Untuk sementara, kita ikuti saja pembagian Creswell itu. Lagi pula, pembagian itu hanyalah latar belakang yang membantu kita mengetahui posisi dan kekhasan penelitian fenomenologis. Penelitian fenomenologis itu sendiri sebenarnya masih terbagi lagi menjadi beberapa versi. Setiap versi itu tentu saja punya penekanannya masing-masing. Dua versi yang cukup banyak digunakan adalah (1) versi fenomenologis interpretatif dan (2) versi fenomenologis deskriptif. Sebelum sampai ke situ, mari kita perjelas posisi penelitian fenomenologis di antara beberapa pendekatan kualitatif lain yang berkembang dalam psikologi pada khususnya dan ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu kemanusiaan (humaniora) pada umumnya.
A. Penelitian Naratif-biografis
Dalam penelitian naratif-biografis, subjek penelitian hanya berjumlah satu orang. Kedengarannya mudah. Peneliti hanya butuh satu partisipan atau satu subjek untuk penelitiannya. Jumlah satu partisipan tidak berarti bahwa penelitian akan berjalan cepat dan mudah. Tujuan dari penelitian naratif-biografis adalah mengungkap peristiwa-peristiwa hidup yang penting dan bermakna pada seorang subjek atau partisipan sehingga muncul pemahaman tentang apa saja yang membuatnya menjadi pribadi seperti saat ini. Perhatikan yang dikatakan Brian Roberts (2002:6) tentang penelitian biografis berikut ini.
Teks Asli
The study of biographical research rests on a view of individuals as creators of meanings which form the basis of their everyday lives. Individuals act according to meanings through which they make sense of social existence.
Transkreasi
Penelitian biografis bersandar pada pandangan individu-individu sebagai pencipta makna di mana makna itu menjadi dasar bagi kehidupan mereka sehari-hari. Individu-individu bertindak menurut makna itu. Lewat makna itu, mereka memberi arti untuk eksistensi sosial mereka.
BAB I Pendekatan Fenomenologis dalam Penelitian Kualitatif 5
Setiap orang menjalani hidupnya dengan macam-macam peristiwa hidup. Apa yang terjadi dalam perjalanan pribadi hidup kita akan berpengaruh dalam cara kita berelasi dengan lingkungan sekitar kita. Beberapa peristiwa hidup begitu membekas dan punya kekuatan untuk mengubah haluan hidup seseorang. Peristiwa seperti itu disebut epifani. Perhatikan lagi apa yang ditulis Barbara Merrill dan Linden West (2009:29) tentang epifani berikut ini.
Teks Asli
Epiphanies are interactional moments and experiences which leave marks on people’s lives. In them, personal character is manifested. They are often moments of crisis which alter the fundamental meaning and structures in a person’s life. Their effects may be positive or negative.
Transkreasi
Epifani-epifani adalah momen-momen atau pengalaman-pengalaman dalam berinteraksi yang meninggalkan bekas dalam kehidupan seseorang. Dalam epifani-epifani itu, karakter pribadi bisa terlihat. Epifani-epifani itu sering kali berupa momen-momen krisis yang mengubah makna dan struktur fundamental dari kehidupan seseorang. Efeknya bisa positif atau negatif.
Dalam melakukan penelitian naratif-biografis, kita tidak harus mencari orang yang terkenal, tetapi mencari orang yang punya sesuatu yang signifikan secara psikologis untuk dibagikan kepada masyarakat. Artinya, ada sesuatu yang penting atau signifikan untuk dipelajari dalam “dunia kehidupan” dari satu orang itu. Karena itu, penelitian biografis menarik untuk dilakukan terhadap pribadi-pribadi yang kita anggap kuat dan bisa menjadi model atau contoh bagi masyarakat. Di masa kuliah S1 dahulu, saya pernah bertemu dengan seorang ibu single parent (orang tua tunggal) yang sudah berusia 60 tahun. Dia menjadi tulang punggung keluarga untuk tiga anaknya sejak ditinggalkan oleh suaminya di usia 27 tahun. Ada banyak cerita atau kisah hidup yang disampaikan kepada saya dalam potongan-potongan percakapan di banyak kesempatan. Sayangnya, saya tidak punya kesempatan untuk melakukan studi biografis pada waktu itu. Padahal, kisah hidupnya menarik untuk diteliti secara biografis.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup6
Meskipun penelitian naratif-biografis membolehkan satu subjek penelitian, perlu selalu diingat bahwa peneliti memerlukan penggalian data yang mendalam. Peneliti naratif-biografis dituntut untuk merancang pertemuan yang intens dengan subjek atau partisipan, menjalankan wawancara dan observasi langsung dengan waktu yang cukup panjang. Semua itu bertujuan mengungkap rangkaian momen dan peristiwa-peristiwa hidup (epifani) yang membentuk kehidupan subjek menjadi seperti saat ini.
B. Penelitian Grounded Theory
Berbeda dengan pendekatan naratif-biografis yang memiliki jumlah subjek tunggal, penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory memiliki subjek yang relatif banyak. Jumlah yang sejauh ini umum saya temui adalah lebih dari 12 partisipan. Jumlah yang banyak itu sangat bisa dimengerti karena peneliti ingin membangun teori, yaitu pengetahuan ilmiah yang bisa diterapkan dalam banyak situasi. GT sebagai penelitian yang ingin mengembangkan teori harus punya kekuatan untuk diterapkan dalam banyak situasi sehingga wajar bila data dikumpulkan dari banyak sumber.
Bila dilihat sejarahnya, GT pada awalnya dikembangkan oleh Barney Glaser and Anselm Strauss di tahun 1960-an. Dalam perkembangannya, kedua sosiolog itu memiliki perbedaan pendapat tentang cara menjalankan GT. Hunter dan Kelly (2008:87) bercerita sebagai berikut.
Teks Asli
Having proposed the research methodology, Glaser and Strauss subsequently disagreed over its precise application which led to three different approaches to grounded theory (Esteves et al., 2002). These are: Glaser and Strauss (1967); Strauss and Corbin (1990) and Glaser’s (1978, 1992) interpretation. The principal distinction between approaches is that Glaser predicates that there should not be a conceived theory in mind, whereas Strauss and Corbin (1998)
Transkreasi
Setelah (bekerja sama) mengemukakan metodologi penelitian [untuk GT], Glaser dan Strauss kemudian berbeda pendapat tentang seperti apa persisnya cara menerapkan grounded theory. Perbedaan ini kemudian memunculkan tiga versi dalam GT, yaitu (1) GT versi Glaser dan Strauss, (2) GT versi Strauss dan Corbin, dan (3) GT versi Glaser. Perbedaan pokok di antara versi-versi itu adalah bahwa Glaser memandang peneliti tidak harus
BAB I Pendekatan Fenomenologis dalam Penelitian Kualitatif 7
highlight then requierement for a theoretical statement to enable and explanation or prediction of theory.
memiliki pandangan-pandangan teoretis dalam benaknya; sementara Strauss dan Corbin menganggap penting pandangan-pandangan teoretis sebagai prasyarat untuk bisa membuat penjelasan atau prediksi teori.
Oleh karena itu, kita tidak perlu heran bila bertemu dengan perbedaan pendapat mengenai perlu atau tidak perlunya teori dalam penelitian kualitatif. Masing-masing pendapat punya alasannya sendiri. Pendukung “perlunya teori” menganggap kita perlu tahu teori yang berkembang untuk bisa menjelaskan temuan penelitian kita di tengah teori yang berkembang; sementara pendukung “tidak perlunya teori” menganggap kita cukup berfokus pada suara-suara asli dari partisipan dalam penelitian tanpa harus terganggu dan terpengaruh oleh “suara-suara teoretis”.
Belakangan ini, berkembang lagi satu versi GT yang cukup populer digunakan, yaitu versi GT dari Kathy Charmaz yang oleh banyak kalangan dianggap cukup jelas prosedurnya. Charmaz mengembangkan pendekatan GT yang berbasis pada perspektif konstruktivis. Perspektif konstruktivis menyatakan bahwa manusia menyusun (mengonstruksi) pemahamannya tentang dunia (lingkungan sekitar) berdasarkan pengalaman hidupnya. Dalam psikologi, perspektif ini lebih sering dibicarakan dalam psikologi pendidikan, khususnya lewat teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget dan Lev Semyonovich Vygotsky.
Di sini, saya tidak perlu berbicara lebih jauh tentang perbedaan di antara berbagai versi GT itu. Perbedaan pandangan seperti itu adalah hal biasa dalam dunia akademis. Untuk itu, mari kita fokus pada apa yang menjadi ciri umum dari GT. Berikut ini adalah definisi GT dari Glaser (1992:16) yang sering digunakan.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup8
Teks Asli
a general methodology of analysis linked with data collection that uses a systematically applied set of methods to generate an inductive theory about a substantive area.
Transkreasi
suatu metodologi umum dalam analisis data yang terkait dengan pengumpulan data yang menggunakan serangkaian metode yang diterapkan secara sistematis untuk memunculkan teori induktif tentang suatu bidang [topik penelitian] yang substantif [dirasakan amat penting]”.
Perhatikan istilah “generate inductive theory (memunculkan teori induktif )”. Artinya, peneliti GT bertujuan membangun teori secara induktif. Dalam filsafat, kita mengenal istilah “penalaran deduktif (deduksi)” dan “penalaran induktif (induksi)”. Penalaran deduktif bermula dari penyataan umum menuju pernyataan-pernyataan spesifik; sementara penalaran induktif bermula dari pernyataan-pernyataan spesifik menuju pernyataan umum. Dalam riset, pendekatan deduktif bermula dari teori sebagai penyataan umum yang ingin diuji atau diperiksa kebenarannya pada data-data spesifik; sementara pendekatan induktif bermula dari data-data spesifik menuju perspektif yang umum atau teori. Pendekatan deduktif umumnya diasosiasikan dengan penelitian kuantitatif dan pendekatan induktif umumnya diasosiasikan dengan penelitian kualitatif.
Nah secara induktif, penelitian kualitatif dengan GT bermaksud mem-ba ngun teori berdasarkan data-data spesifik yang dikumpulkan langsung dari partisipan-partisipan di lapangan. Dengan menjalankan proses induktif, peneliti GT mengumpulkan banyak informasi dari berbagai sumber di lapangan. Informasi yang banyak itu kemudian dianalisis sebelum akhirnya disimpulkan. Kesimpulan umum yang didapatkan itu bisa dianggap sebagai temuan teoretis.
Mengapa harus membangun teori secara induktif ? Umumnya, upaya untuk membangun teori muncul karena keterbatasan teori atau literatur yang tersedia mengenai topik tertentu. Berikut ini adalah contoh klasik yang bisa memperjelas alasan grounded theory diperlukan.
BAB I Pendekatan Fenomenologis dalam Penelitian Kualitatif 9
Sosiolog Glaser dan Strauss dan seorang perawat yang bernama Jeanne Quint mengadakan penelitian selama enam tahun di enam lokasi rumah sakit. Mereka bermaksud memahami tentang proses kematian (dying) dan berharap bisa memberi sumbangan teoretis [tujuan penelitian] yang membantu memahami proses kematian. Belum ada literatur tentang proses kematian pada waktu itu [topik yang masih langka]. Mereka mengkaji macam-macam aspek dari proses kematian. Mereka mengikuti dokter, pasien, perawat, dan staf rumah sakit [partisipan yang multisumber]. Mereka menyaksikan bagaimana mereka bekerja [pengumpulan data dengan observasi] dan mengajukan pertanyaan [pengumpulan data dengan wawancara]. Pada akhirnya, mereka memunculkan teori [hasil penelitian] tentang proses kematian berdasarkan data-data dari dokter, pasien, keluarga, dan perawat.
Ada tiga tahapan penting dalam GT, yaitu (1) mengumpulkan data, (2) memproses data, dan (3) mengembangkan teori. Proses pengumpulan data berjalan secara dinamis. Maksud dari “dinamis” itu begini: Setelah mengumpulkan data, kita melakukan analisis dan bila dalam analisis itu ditemukan kekurangan data, kita bisa kembali mengumpulkan data sampai kita merasa cukup. Rasa “sudah cukup” ini disebut saturasi data. Dalam bahasa Latin, saturare yang berarti mengisi sampai penuh, merasa puas. Saturasi data berarti keadaan di mana peneliti sudah merasa maksimal dan puas dengan data yang didapatkan.
Di antara pengumpulan data (tahap 1) dan pengembangan teori (tahap 3), ada tahap yang sangat penting, yaitu analisis data dengan menjalankan coding (pemberian kode). Apakah coding itu? Mari kita perhatikan yang ditulis oleh Cathy Charmaz (2006:46) berikut ini.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup10
Teks Asli
Coding is the pivotal link between collecting data and developing an emergent theory to explain these data. Through coding, you define what is happening in the data dan begin to grapple with what it means. The codes take form together as elements of a nascent theory ….
Transkreasi
Coding (pemberian kode untuk data) adalah penghubung (jembatan) yang sangat penting antara pengumpulan data dan pengembangan teori dari data. Melalui coding, peneliti mendefinisikan apa yang terjadi dalam data dan mulai bergulat dengan makna dari data itu. Hasil dari coding itu membentuk elemen-elemen dari teori yang bakal muncul ….
Coding (pemberian kode) itu sendiri berjalan dalam tiga tahapan yang umum ditemui dalam literatur GT, yaitu (1) open coding, (2) axial coding, dan (3) selective coding. Tahapan itu mencerminkan pergerakan dari (1) data yang banyak, (2) memadat, lalu (3) mengerucut pada gagasan pokok dari seluruh data. Gagasan pokok itulah yang yang kemudian dikembangkan menjadi teori. Kita tidak mungkin membicarakan ketiga tahap coding itu di sini. Cukup diingat bahwa coding itu menentukan penemuan teori.
Harapan dari GT adalah munculnya teori baru yang bisa mengisi kekosongan atau kekurangan literatur. Oleh karena itu, peneliti kualitatif yang menggunakan GT diharapkan melakukan survei literatur terlebih dahulu untuk yakin betul bahwa topik penelitiannya memang masih relatif baru dan belum dibicarakan dalam literatur yang tersedia. Bisa diasumsikan bahwa seorang peneliti GT adalah peneliti yang bacaan literaturnya luas (ekstensif ) sehingga bisa merasakan kurang atau belum adanya teori yang berbicara tentang topik tertentu.
GT bisa menjadi pendekatan kualitatif yang diterapkan dalam banyak bidang psikologi, seperti psikologi pendidikan, psikologi organisasi, psikologi perkembangan, atau psikologi klinis. Salah satu contoh GT dalam psikologi pendidikan adalah A Grounded Theory Study of the Multicultural Experiences of School Psychologists (Penelitian Grounded Theory tentang Pengalaman Multikultural dari Psikolog-psikolog Sekolah) yang dilakukan oleh Kenya Noreen Mewborn. Penelitian GT ini menggali pengalaman psikolog-psikolog sekolah yang bekerja di beberapa sekolah yang murid-muridnya
BAB I Pendekatan Fenomenologis dalam Penelitian Kualitatif 11
berbeda secara etnis dan rasial. Data didapatkan dari 10 psikolog sekolah dan 8 anggota staf yang bekerja dengan psikolog-psikolog sekolah itu. Analisis data menghasilkan sejumlah poin penting yang terkait dengan upaya-upaya yang dijalankan oleh para psikolog sekolah saat bekerja dalam situasi sekolah yang multikultural.
Apakah Anda tertarik? Saya kira, penelitian GT ini lebih cocok untuk S3. Untuk level S1 atau S2, tidak disarankan karena mahasiswa masih cenderung dibebani pemahaman teoretis dasar plus desakan kampus dan orang tua yang sering kali meminta mahasiswa lulus dengan cepat.
C. Studi Kasus
Studi kasus punya sejarah yang panjang dan digunakan secara bervariasi dalam beberapa disiplin ilmu. Dalam disiplin kedokteran, kita mengenal studi kasus yang umumnya terkait dengan rekaman-rekaman klinis dari praktisi medis, seperti studi kasus hipertensi atau studi kasus psoriasis. Dalam psikologi, kita juga mengenal studi kasus untuk penggalian informasi yang dalam tentang dinamika psikis di balik gangguan psikologis, seperti kasus Little Hans (kasus tentang anak laki-laki bernama Hans yang berusia 5 tahun dan mengalami fobia kuda) dan kasus Anna O (kasus tentang wanita yang menderita histeria) yang dilakukan Sigmund Freud. Dalam ilmu hukum pun dikenal studi kasus, seperti studi kasus hukum pidana untuk aborsi atau studi kasus hukum perdata untuk perebutan harta warisan. Dengan contoh-contoh itu, saya hanya ingin mengatakan bahwa studi kasus pada dasarnya bervariasi.
Ada beberapa ciri yang menyatukan macam-macam studi kasus dari beberapa disiplin ilmu. Salah satu ciri yang umum dari studi kasus adalah penekanan pada proses pengumpulan data yang multisumber. Multisumber berarti peneliti membutuhkan banyak sumber data yang berbeda, seperti hasil tes psikologis, foto, observasi, wawancara, catatan harian, data-data dari media sosial, dan lain lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan yang ditulis oleh tokoh penting dalam studi kasus Robert K. Yin (2003:83) berikut ini.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup12
Teks Asli
Case study evidence may come from six sources: documents, archival records, interviews, direct observation, participant-observation, and physical artifacts.Using these six sources calls for mastering different data collection procedures. Throughout, a major objective is to collect data about actual human events and behavior. This objective differs from (but complements) the typical survey objective of capturing perceptions, attitudes, and verbal reports about events and behavior (rather than direct evidence about the events and behavior).
In addition to the attention given to the six sources, some overriding principles are important to any data collection effort in doing case studies. These include the use of (a) multiple sources of evidence (evidence from two or more sources, converging on the same facts or findings), (b) a case study database (a formal assembly of evidence distinct from the final case study report), and (c) a chain of evidence (explicit links among the questions asked, the data collected, and the conclusions drawn). The incorporation of these principles into a case study will increase its quality substantially.
Transkreasi
Bukti [data] dalam studi kasus bisa berasal dari enam sumber, yaitu (1) dokumen, (2) rekaman-rekaman arsip, (3) interviu (wawancara), (4) observasi langsung, (5) observasi-partisipan, dan (6) artefak-artefak fisik. Untuk menggunakan keenam sumber ini, peneliti perlu menguasai prosedur pengumpulan data yang berbeda. Secara keseluruhan tujuan utama dari pengumpulan data adalah mengumpulkan data tentang peristiwa-peristiwa dan perilaku aktual yang terjadi pada manusia. Tujuan studi kasus tidak sama dengan tujuan dari survei. Tujuan survei secara khusus ingin menangkap persepsi, sikap, dan laporan verbal tentang peristiwa atau perilaku. Studi kasus lebih condong pada upaya mendapatkan bukti langsung tentang perisiwa atau perilaku. Bagaimanapun, tujuan studi kasus bisa melengkapi tujuan survei.
Selain keenam sumber itu, ada beberapa prinsip utama dalam upaya yang perlu diperhatikan dalam mengumpulkan data dalam studi kasus. Prinsip-prinsip ini meliputi penggunaan: (a) sumber-sumber bukti yang jamak atau beragam (bukti berasal dari dua atau lebih sumber, yang menyatukan fakta-fakta atau temuan-temuan yang sama), (b) database studi kasus (kumpulan bukti formal saat membuat laporan akhir studi kasus), dan (c) rantai bukti
BAB I Pendekatan Fenomenologis dalam Penelitian Kualitatif 13
(hubungan eksplisit di antara pertanyaan yang diajukan, data yang dikumpulkan, dan kesimpulan yang ditarik). Penyatuan prinsip-prinsip penting dalam meningkatkan kualitas studi kasus.
Saya kira, informasi pokok tentang studi kasus yang diberikan Yin di atas sudah cukup jelas. Semua sumber data dalam studi kasus bisa dihubungkan satu sama lain untuk membentuk pemahaman kita yang lebih menyeluruh tentang suatu kasus. Jadi, semua data itu pada dasarnya bersifat komplementer (saling melengkapi). Wawancara pada satu orang, misalnya, bisa melengkapi kekurangan informasi yang didapatkan saat mewawancarai orang yang lain. Dalam studi kasus, istilah yang lebih sering digunakan untuk orang yang diwawancarai adalah informan (orang yang memberi informasi).
Studi kasus adalah studi atau penelitian tentang kasus. Sejauh ini, kita sudah berbicara tentang studi kasus tanpa memperjelas makna sebenarnya dari “kasus” dalam studi kasus? Mari kita perhatikan lagi yang ditulis Robert K. Yin (2003:12) berikut ini dalam memperluas pendapat Schramm tentang arti dari kasus.
Teks Asli
The essence of a case study, the central tendency among all types of case study, is that it tries to illuminate a decision or set of decisions: why they were taken, how they were implemented, and with what result. (Schramm,1971, emphasis added) This definition thus cites cases of “decisions” as the major focus of case studies. Other common cases include individuals, organizations, processes, programs, neighborhoods, institutions, and even events.
Transkreasi
Bila kita melihat kecenderungan umum dari semua tipe studi kasus, maka esensi atau inti dari studi kasus adalah bahwa studi kasus berusaha menjelaskan keputusan atau serangkaian keputusan; mengapa keputusan itu diambil, bagaimana penerapan keputusan itu dan hasil dari keputusan itu. Definisi yang dikemukakan Schramm (1971) itu menyebutkan bahwa “keputusan” adalah fokus utama dari macam-
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup14
macam studi kasus. Kasus-kasus lain yang umum ditemui adalah kasus yang terhubung dengan individu, organisasi, program, lingkungan sekitar, institusi, dan bahkan kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa.
Jadi, arti “kasus” dalam studi kasus umumnya mengarah pada keputusan, individu, organisasi, program, daerah, institusi (lembaga), atau kejadian/peristiwa. Di antara macam-macam makna kasus itu, keputusan adalah makna yang dominan digunakan. Mari kita perjelas saja dengan contoh. Kita, misalnya, ingin meneliti kasus tentang keputusan fakultas psikologi menerapkan kurikulum yang diberi nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di Fakultas Psikologi. Agar dapat menghimpun data tentang “kasus [keputusan] penerapan sistem KBK”, maka peneliti akan mewawancarai sumber-sumber informasi (informan), seperti dekan, dosen, staf tata usaha, atau mahasiswa. Peneliti juga bisa mengobservasi aktivitas mahasiswa dan dosen di kelas. Contoh lain lagi, seorang mahasiswa melakukan studi kasus yang berjudul “Studi kasus tentang Resosialisasi Eks-pasien Skizofrenia Paranoid”. Apa yang menjadi kasusnya? Program Resosialisasi. Pengumpulan datanya tentu multisumber: dokter rumah sakit jiwa (RSJ), psikolog RSJ, orang tua, saudara, perawat, hasil diagnosis, catatan perkembangan, foto, dan lain-lain.
Jika Robert Yin menyatakan bahwa ada enam sumber informasi dalam studi kasus, itu tidak berarti keenam sumber itu harus ada dalam satu studi kasus. Dapat terjadi bahwa peneliti hanya menggunakan informasi yang didapatkan lewat wawancara. Hasil wawancara dari seluruh partisipan akan saling melengkapi dalam memberi jawaban untuk kasus yang sedang diteliti. Contoh studi kasus yang hanya mengandalkan metode wawancara adalah penelitian Chris Holligan (1997) yang berjudul “Theory in initial teacher education: students’ perspectives on its utility–a case study (Teori dalam pendidikan awal menjadi guru: perspektif mahasiswa tentang manfaat pendidikan mereka—sebuah studi kasus)”. Penelitian itu bertujuan membangun pemahaman tentang pendidikan awal menjadi guru. Holligan hanya menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara semi-
BAB I Pendekatan Fenomenologis dalam Penelitian Kualitatif 15
terstruktur pada 40 mahasiswa sarjana pendidikan (Bachelor of Education). Masing-masing mahasiswa diwawancarai selama dua jam. Informasi dari seluruh mahasiswa itu saling melengkapi dalam membantu peneliti membangun teori tentang pendidikan awal menjadi guru. Studi kasus ini menunjukkaan bahwa penerapan pengumpulan data dalam studi kasus cukup beragam.
D. Penelitian Etnografis
Penelitian etnografis atau kadang-kadang cukup disebut “etnografi” adalah pendekatan yang dulunya akrab dengan antropologi. Pada awalnya, kajian etnografis banyak dilakukan pada suku-suku pedalaman (etnos). Salah satu peneliti awal yang memelopori etnografi adalah Bronislaw Malinowski, antropolog Polandia yang terkenal lewat monografnya tentang masyarakat di Kepulauan Trobriand (Trobriand Islands). Malinowski mendapatkan gelar doktornya di bidang fisika dan matematika. Sayangnya, ada kendala fisik yang menghambatnya berkarier dalam bidang keilmuan yang sudah ditekuninya itu. Malinowski lalu menggeser haluan. Dia sempat bekerja di Universitas Leipzig, Jerman, dan membantu Wilhelm Wundt, “Bapak psikologi modern”.
Secara pribadi, Malinowski punya ketertarikan khusus pada antropologi. Pada tahun 1915, dia mengikuti ekspedisi ke Papua New Guinea yang diselenggarakan oleh Pemerintah Inggris. Di Papua New Guinea, dia tinggal di Kepulauan Trobriand selama dua tahun. Pengalaman tinggal bersama masyarakat di kepulauan itu kemudian ditulis menjadi karya besar di bidang antropologi dengan judul Argonauts of the Western Pacific (Petualang-petualang Laut dari Pasifik Barat). Karya itu menjadi salah satu dasar penting untuk penelitian etnografis. James G. Frazer yang memberi pengantar untuk buku Malinowski (2005: v) itu menulis berikut ini.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup16
Teks Asli
In the Trobriand Islands, to the east of New Guinea, to which he next turned his attention, Dr. Malinowski lived as a native among the natives for many months together, watching them daily at
Transkreasi
Di kepulauan Trobriand, sebelah Timur Papua New Guinea, yang kemudian menjadi wilayah risetnya, Malinowski tinggal sebagai penduduk asli di antara penduduk asli selama
work and at play, conversing with them in their own tongue, and deriving all his information from the surest sources-personal observation and statements made to him directly by the natives in their own language without the intervention of an interpreter. In this way he has accumulated a large mass of materials ...
berbulan-bulan [observasi partisipan], menyaksikan mereka setiap hari saat bekerja dan bermain [catatan-catatan lapangan], berbincang-bincang dengan mereka dalam bahasa lokal [wawancara langsung] dan mengambil semua datanya dari sumber-sumber yang paling terpercaya [informan kunci]—observasi pribadi dan pernyataan-pernyataan langsung didapatkannya dari penduduk lokal dalam bahasa lokal tanpa menggunakan penerjemah. Dalam cara ini, dia telah mengumpulkan banyak sekali materi …
Dalam cerita itu, tergambar aktivitas pokok dalam penelitian etnografis di bidang antropologi. Penelitan etnografis dalam antropologi memang tidak sama dengan penelitian etnografis dalam psikologi. Meski demikian, ciri umum dari penelitian etnografis adalah deskripsi yang mendetail yang biasanya berdampak pada laporan yang tebal. Deskripsi itu bersumber dari wawancara dengan informan kunci (key informants), observasi partisipan (participant observation), dan catatan-catatan lapangan (field notes) selama observasi. Observasi dan pencatatan lapangan dijalankan secara ketat. Artinya, ada langkah-langkah sistematis dalam mencatat dan merekam data. Data etnografis bisa berupa peristiwa, perilaku, atau artefak. Tujuan dari penelitian etnografis adalah memberi deskripsi yang berisi informasi tentang perspektif orang dalam (insider’s perspective).
BAB I Pendekatan Fenomenologis dalam Penelitian Kualitatif 17
Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang menyentuh semua bangsa dan lapisan masyarakat, istilah etnos (suku) mengalami pergeseran. Saya teringat dengan teman saya di Belgia yang bercerita tentang teman kuliahnya yang ditegur oleh dosen pengujinya di ruang sidang karena menggunakan istilah “masyarakat primitif ”. Dosen itu, dalam cerita teman saya tadi, berpendapat bahwa sekarang ini sudah tidak ada masyarakat primitif karena semuanya sudah tersentuh teknologi. Saya kira, kita bisa sepakat bahwa masyarakat memang sudah mengalami pergeseran akibat kemajuan teknologis. Di zaman “mesin-mesin pintar (smart machines)” saat ini, kita sudah tidak lagi mengenal masyarakat primitif dalam pengertian masyarakat terbelakang secara teknologis. Semua kelompok masyarakat sudah tersentuh teknologi. Nah, suku-suku pedalaman yang dahulu banyak menjadi subjek studi etnografis sudah bergeser menjadi komunitas-komunitas yang berkembang dalam masyarakat kita saat ini, seperti komunitas fotografi, komunitas motor gede (moge), dan banyak lagi komunitas pecinta ini dan itu.
Bidang psikologi yang sejauh ini banyak memanfaatkan penelitian etnografis ini adalah psikologi industri dan psikologi komunitas. Bidang-bidang psikologi lain tentu saja bisa memanfaatkan peluang untuk melakukan kajian etnografis. Fokus kita dalam kajian etnografis adalah mengangkat nilai-nilai (values) yang berkembang dalam suatu komunitas. Kita ingin mendeskripsikan bagaimana suatu komunitas atau kelompok hidup oleh nilai-nilai yang mereka anut bersama (shared values). Dalam mengumpulkan data, peneliti etnografis banyak mengandalkan wawancara dan observasi. Contoh dari penelitian etnografis yang bisa dilakukan adalah Studi Etnografis tentang Komunitas Gay. Agar riset bisa berjalan lancar, peneliti etnografis perlu diterima dahulu dalam komunitas gay agar bisa leluasa melakukan pengumpulan data.
E. Penelitian Fenomenologis
Kita sekarang sampai ke pendekatan yang selanjutnya: penelitian fenomenologis. Pendekatan ini sengaja saya bicarakan paling akhir karena keterhubungannya yang erat dengan psikologi sebagai ilmu tentang proses mental dan perilaku. Fenomenologi terkait dengan istilah “fenomena”.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup18
Jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kita akan mendapatkan makna fenomena sebagai berikut.
fenomena/fe·no·me·na/ /fénoména/ n 1 hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam); gejala: gerhana adalah salah satu -- ilmu pengetahuan; 2 sesuatu yang luar biasa; keajaiban: sementara masyarakat tidak percaya akan adanya pemimpin yang berwibawa, tokoh itu merupakan -- tersendiri; 3 fakta; kenyataan: peristiwa itu merupakan -- sejarah yang tidak dapat diabaikan.
Di antara ketiga arti tersebut, saya tidak menemukan makna yang pas untuk menjelaskan arti “fenomena” dalam fenomenologi. Jadi, kita tidak perlu bersusah payah mencocok-cocokkan fenomena dalam kamus dengan fenomena dalam fenomenologi. Kamus memang sering kali membantu pemahaman, tetapi untuk istilah “fenomena” dalam fenomenologi, definisi dari kamus kita kesampingkan dahulu.
Dalam fenomenologi, fenomena berarti penampakan/kemunculan se-suatu bagi kesadaran. Bila ditelusuri asal-muasalnya, istilah “fenomena” itu berasal dari kata Yunani “phainomenon (φαινόμενον)” yang berarti penam-pakan sesuatu (appearance of things). Bentuk jamak dari phainómenon adalah “phainomena (φαινόμενα)”. Saya ulangi: phainomenon adalah bentuk tunggal dan phainomena adalah bentuk jamak. Bila disimak, ada kejanggalan di situ. Dalam bahasa Indonesia, kita menyerap bentuk jamak (phainomena) dan menjadikannya bentuk tunggal (fenomena) yang kemudian dijamakkan menjadi fenomena-fenomena. Peristiwa bahasa itu cukup sering ditemui dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Yunani, criteria adalah bentuk jamak dari criterion, tetapi bahasa Indonesia menyerap criteria (bentuk jamak) dan menjadikannya bentuk tunggal (kriteria) yang kemudian dijamakkan menjadi kriteria-kriteria. Kata Latin data adalah bentuk jamak dari datum, tetapi bahasa Indonesia menyerap data (bentuk jamak) untuk bentuk tunggal dan kemudian dijamakkan menjadi data-data. Pesan intinya adalah bahwa dalam bahasa Indonesia, fenomena adalah bentuk tunggal dan bentuk jamaknya adalah fenomena-fenomena. Kita terima saja penyerapan yang keliru dan sudah terlanjur menyebar luas itu.
BAB I Pendekatan Fenomenologis dalam Penelitian Kualitatif 19
Mari kita kembali ke fenomena dalam fenomenologi. Jika fenomena berarti penampakan sesuatu, apakah sesuatu itu? Sesuatu itu adalah apa saja yang tampak/muncul bagi kesadaran.
Saat Anda duduk melihat/menyadari bulan purnama, maka bulan purnama adalah fenomena (sesuatu yang tampak bagi kesadaran Anda).
Saat Newton duduk santai dan melihat/menyadari buah apel yang jatuh, maka peristiwa jatuhnya buah apel itu adalah fenomena (sesuatu yang tampak bagi kesadaran Newton).
Saat Ganjar melihat/menyadari anaknya yang sedang bermain, maka aktivitas anak yang sedang bermain itu adalah fenomena (sesuatu yang tampak bagi kesadaran Ganjar).
Saat Salma melihat/menyadari sekelompok orang tertawa, maka tawa dari sekelompok orang itu adalah fenomena (sesuatu yang tampak bagi kesadaran Salma).
Saat Ika melihat/menyadari kemacetan panjang, maka kemacetan panjang itu adalah fenomena (sesuatu yang tampak bagi kesadaran Ika).
Saat Mali merasakan gejolak marah dalam dirinya, maka gejolak marah itu adalah fenomena (sesuatu yang tampak bagi kesadaran Mali).
Saat Atha melihat orang berpelukan, maka aktivitas berpelukan itu adalah fenomena (sesuatu yang tampak bagi kesadaran Atha).
Demikianlah, fenomena bisa berupa apa saja yang muncul dalam kesadaran. Fenomena bisa berupa benda (misalnya, bulan purnama), akti vitas manusia (aktivitas bermain pada anak atau aktivitas tertawa pada seke lompok orang), peristiwa luar (misalnya, kemacetan panjang, peristiwa jatuhnya buah apel), peristiwa batin (misalnya, gejolak rasa marah). Jadi, fenomena itu banyak sekali tergantung pada apa yang tampak pada kesadaran seseorang. Sekarang, kita lihat lagi beberapa contoh tentang bagaimana fenomena bisa menjadi judul penelitian fenomenologis.
Calon peneliti melihat seorang ibu yang mempunyai anak yang didiagnosis skizofrenia. Bagi peneliti, ibu yang memiliki anak
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup20
yang didiagnosis skizofrenia adalah fenomena yang muncul dalam kesadaran peneliti. Bagaimana dengan si ibu itu sendiri? Bagi ibu, anak yang didiagnosis skizofrenia adalah fenomena dalam kesadaran ibu. Calon peneliti lalu berpikir: “Ibu itu punya pengalaman memiliki anak yang didiagnosis skizofrenia. Saya ingin meneliti pengalaman ibu yang memiliki anak yang didiagnosis skizofrenia.”
Calon peneliti melihat seorang remaja yang kecanduan pada alkohol. Bagi peneliti, remaja yang kecanduan alkohol adalah fenomena yang muncul dalam kesadaran peneliti. Bagaimana degan si remaja? Bagi si remaja, kecanduan alkohol adalah fenomena yang muncul dalam kesadarannya. Calon peneliti lalu berpikir: “Remaja itu punya pengalaman kecanduan alkohol. Saya ingin meneliti pengalaman remaja yang kecanduan alkohol.”
Calon peneliti melihat seorang penderita sakit ginjal yang menjalani cuci darah (dialisis). Bagi peneliti, peristiwa cuci darah itu adalah fenomena yang muncul dalam kesadaran peneliti. Bagaimana dengan si pasien? Bagi si pasien, peristiwa menjalani cuci adalah fenomena yang muncul dalam kesadarannya. Calon peneliti lalu berpikir: “Pasien itu punya pengalaman cuci darah. Saya ingin meneliti pengalaman pasien yang menjalani cuci darah (dialisis).”
Melalui contoh-contoh tersebut, saya berharap Anda sekarang bisa menjawab saat mendapat pertanyaan: “Fenomena apa yang ingin Anda teliti? Pengalaman ....” Silakan meneruskan sendiri sesuai dengan fenomena apa yang menarik perhatian Anda untuk diteliti.
Dengan melakukan penelitian fenomenologis, kita mau masuk ke dalam pengalaman seseorang dan mau repot dengan fenomena apa saja yang muncul dalam pengalaman orang itu. Peneliti-peneliti psikologi umumnya tertarik dengan fenomena-fenomena psikis atau mental. Untuk keperluan penelitian dalam psikologi pada khususnya dan ilmu-ilmu kemanusiaan pada umumnya, saya mengusulkan untuk menerjemahkan fenomena itu menjadi kejadian mental/peristiwa mental/aktivitas mental. Oleh karena itu, kita bisa mendefinisikan fenomena sebagai berikut.
BAB I Pendekatan Fenomenologis dalam Penelitian Kualitatif 21
Fenomena adalah kejadian mental/peristiwa mental/aktivitas mental yang dialami partisipan/subjek penelitian. Fenomena itu
adalah bagian dari pengalaman hidup partisipan/subjek penelitian.
F. Definisi Populer untuk Fenomenologi
Apa sebenarnya fenomenologi itu? Bagaimana kita mendefinisikannya? Sudah cukup banyak buku tentang fenomenologi yang beredar dan kita bisa menemukan beragam definisi untuk fenomenologi. Di sini, saya mengesampingkan dulu definisi yang berbasis literatur. Saya ingin bertitik tolak dari definisi populer yang beredar di internet. Dalam Kotak 1.2, kita bisa melihat definisi fenomenologi yang ditawarkan Wikipedia.
Kotak 1.2 Definisi Populer untuk Fenomenologi
Sumber: www.wikipedia.org
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup22
Dalam dua halaman Wikipedia tersebut yang diakses tanggal 29 April 2017, kita disodorkan penjelasan terpisah tentang fenomenologi, yaitu (1) fenomenologi dalam filsafat dan (2) fenomenologi dalam psikologi. Saat membuka halaman fenomenologi dalam filsafat, saya diberi keterangan berikut.
“Artikel ini tentang fenomenologi dalam filsafat. Untuk fenome-no logi sebagai metode penelitian, lihat phenomenology. Untuk fenomenologi sebagai pendekatan dalam psikologi, lihat phenomenology (psychology).”
Saat membuka halaman phenomenology (psychology), saya mendapat definisi berikut.
Phenomenology is the study of subjective experience.Fenomenologi adalah penelitian tentang pengalaman [manusia]
yang subjektif.
Kita terima dahulu saja definisi itu sebagai definisi awal yang bisa menjadi alat bantu memahami lebih jauh fenomenologi dalam psikologi. Kata kunci dari penelitian fenomenologis adalah subjektif. Mengapa subjektif ? Bukankah penelitian yang ilmiah itu harus objektif ? Memang, kita harus mengakui bahwa subjektivitas ini rentan dipersoalkan dalam lingkungan akademis karena terkesan bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang menuntut sikap objektif. Peristiwa mental (fenomena mental) yang dialami seseorang memang subjektif. Subjektivitas dalam studi fenomenologis bukan masalah. Bila ada yang mempersoalkan tentang subjektivitas dalam penelitian fenomenologis, kita bisa menanggapinya dengan mengatakan, “Fakta yang paling objektif tentang manusia adalah bahwa manusia itu pada dasarnya subjektif.”
Oleh karena itu, pendekatan fenomenologis lebih cocok menggunakan istilah “intersubjektif ” dari pada menggunakan istilah “objektif ”. Intersubjektif berarti subjektivitas seseorang bisa terhubung dengan subjektivitas orang lain. Dalam keterhubungan itulah, pemahaman muncul.
BAB I Pendekatan Fenomenologis dalam Penelitian Kualitatif 23
• Bagaimanamungkinduaorangyangberbagiceritahidupbisasalingmemahami jika subjektivitasnya tidak terhubung? Orang yang satu bisa memahami kesedihan atau rasa bahagia orang yang lain. Subjektivitas mereka terhubung. Itulah intersubjektif.
• Atha,anaksayayangberusiaempattahun,datangmendekatisayadan mengatakan “Atha sayang Papa”. Subjektivitas saya merasakan subjektivitas anak saya. Karena subjektivitas kami yang “terhubung”, saya mengatakan, “Papa juga sayang Atha”. Anak saya memeluk saya dengan erat. Saya juga memeluknya dengan erat. Subjektivitas kami terhubung. Itulah intersubjektif.
• Seorangpeneliti fenomenologismempunyai tigapartisipan.Pene-liti punya subjektivitasnya sendiri dan ketiga partisipan punya subjek tivitasnya masing-masing. Bagaimana mungkin peneliti feno-menologis bisa memahami pengalaman partisipannya bila sub-jek tivitasnya tidak terkoneksi dengan subjektivitas partisipannya. Pemahaman (understanding) muncul dari keterhubungan subjek-tivitas peneliti dengan subjektivitas partisipannya.
Ada saatnya, kita akan membicarakan intersubjektivitas ini. Untuk se-mentara, kita tinggalkan dulu topik itu dan kembali ke fenomena (peristiwa mental/kejadian mental/aktivitas mental). Fenomena yang bisa dibahas dalam penelitian fenomenologis tidak akan habis. Selalu saja ada fenomena (peristiwa/kejadian/aktivitas mental) yang bisa disoroti.
• Saat kita melihat wanita yang menjalankan peran ibu sekaliguswanita karier, maka fenomena yang muncul adalah “(aktivitas) menjadi ibu sekaligus wanita karier”.
• Saatkitamelihatsiswa-siswayangbelajardipesantren,makafeno-mena yang muncul adalah “(aktivitas) belajar di pesantren”.
• Saat kitamelihat orang yangmenjalani persalinan pertama,makafenomena yang muncul adalah “(peristiwa) persalinan pertama”.
Fenomena tertentu bisa menjadi bagian dari pengalaman hidup saya dan bukan bagian dari pengalaman hidup Anda. Begitu juga sebaliknya, fenomena tertentu adalah bagian dari pengalaman hidup Anda dan bukan bagian dari pengalaman hidup saya. Dalam fenomenologi, pengalaman hidup manusia
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup24
itu sering kali diistilah “the lived experience (pengalaman yang dialami langsung)”. Jika kita membuka Google lalu mengetik “the lived experience of+pdf ”, maka kita akan disodori banyak judul penelitian fenomenologis yang berupa jurnal, tesis, atau disertasi, seperti yang terlihat dalam Kotak 1.3.
Kotak 1.3 Penelusuran Online untuk Judul The Lived Experience
BAB I Pendekatan Fenomenologis dalam Penelitian Kualitatif 25
Sumber: www.google.com
Jika fenomenologi adalah penelitian tentang pengalaman subjektif, mau diapakan pengalaman subjektif itu oleh peneliti fenomenologis? Di bagian awal bab ini, saya sempat menyinggung dua versi pendekatan fenomenologis dalam psikologi, yaitu (1) versi fenomenologis interpretatif dan (2) versi fenomenologis deskriptif.
• Dalam pendekatan fenomenologis interpretatif, peneliti ingin meng-interpretasikan/menafsirkan bagaimana setiap partisipan memberi arti untuk pengalamannya (misalnya, menjadi ibu sekaligus wanita karier). Muara dari interpretasi itu adalah laporan tentang penga-laman unik masing-masing partisipan dan bagaimana keunikan itu terhubung.
• Dalam pendekatan fenomenologis deskriptif, peneliti ingin mendes-kripsikan/menggambarkan bagaimana setiap partisipan memberi arti untuk pengalamannya (misalnya, menjadi ibu sekaligus wanita karier). Muara dari deskripsi itu adalah paham apa inti/esensi dari pengalaman seluruh partisipan (misalnya, apa inti/esensi dari pengalaman menjadi ibu sekaligus wanita karier).
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup26
G. Kemunculan Penelitian Fenomenologis
Sejarah munculnya “penelitian fenomenologis” dalam psikologi sangat mudah ditelusuri. Penelitian fenomenologis berakar pada fenomenologi (filsafat fenomenologis). Edmund Husserl, Bapak fenomenologi, memang dengan jelas sekali mengaitkan filsafat fenomenologis dan psikologi. Dalam buku “Ideas pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological philosophy (Ide-ide yang terkait dengan fenomenologi murni dan filsafat fenomenologis)”, Husserl (1980:19-60) mengkhususkan satu bab yang panjang untuk berbicara tentang keterkaitan fenomenologi dan psikologi (lihat Kotak 1.4).
Kotak 1.4 Bab buku Husserl tentang hubungan psikologi dan fenomenologi
Sumber: Edmund Husserl, 1980: 65
Di awal berdirinya psikologi modern, filsafat sebenarnya tidak dilepaskan dari psikologi. Beberapa buku sejarah psikologi sudah keliru menyatakan bahwa psikologi menjadi psikologi modern dan ilmiah setelah bebas atau merdeka dari filsafat. Psikologi modern yang menjadi disiplin yang mandiri di akhir tahun 1800-an tetap berinteraksi dengan filsafat sampai sekarang. Kita lupa bahwa jurnal psikologi yang pertama kali terbit diberi nama “Philosophische Untersuchungen (Penelitian-penelitian Filosofis)” oleh Wilhelm Wundt, “Bapak psikologi modern” . Kita bisa bertanya, mengapa Wundt tidak menyebutnya Psychologische Untersuchungen (penelitian-penelitian psiko logis)? Jelas, interaksi psikologi dan filsafat dianggap perlu dalam mengiringi perkembangan psikologi modern. Interaksi antara psikologi dan filsafat fenomenologis bisa dijelaskan sebagai berikut.
BAB I Pendekatan Fenomenologis dalam Penelitian Kualitatif 27
• Psikologi umumnya didefinisikan sebagai ilmu tentang proses mental dan perilaku.
• Filsafatfenomenologis(fenomenologi)adalahkajiantentangfeno-mena (peristiwa/kejadian/ aktivitas mental).
• Penelitianfenomenologisadalahpenelitiantentangfenomena (pe-ris tiwa/kejadian/aktivitas mental) dalam macam-macam penga-laman hidup seseorang.
Oleh karena itu, bisa dimengerti mengapa fenomenologi akrab dengan psikologi dan mengapa beberapa tokoh yang terkenal dalam psikologi belajar dan menerapkan fenomenologi dalam karier akademis dan profesional mereka. Beberapa dari tokoh itu akan kita bicarakan sekilas di sini.
• Carl Stumpf adalah peneliti awal di bidang psikologi musik. Diahidup sezaman dengan Wilhelm Wundt yang dikenal sebagai Bapak psikologi modern. Bagi kebanyakan mahasiswa psikologi, Wilhelm Wundt jauh lebih terkenal daripada Carl Stumpf. Padahal, Stumpf juga melakukan riset-riset laboratorium di Insititut Psikologi Berlin di mana dia menjadi direkturnya. Stumpf adalah murid Franz Brentano, filsuf yang menginspirasi lahirnya fenomenologi. Edmund Husserl, Bapak fenomenologi, mengakui pengaruh Brentano dan Stumpf bagi fenomenologinya. Dalam buku Husserl yang berjudul Logische Untersuchungen (Logical Investigations/Penelitian-penelitian Logis), Husserl menulis di halaman pembuka “Dedicated to Carl Stumpf (Dipersembahkan untuk Carl Stumpf )”. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah fakta bahwa Stumpf adalah inspirator bagi munculnya psikologi Gestalt yang banyak berbicara tentang hukum-hukum persepsi manusia.
• Sigmund Freud, peletak dasar psikoanalisis, berkenalan dengangagasan-gagasan dasar fenomenologi lewat kuliah-kuliah Franz Brentano. Dalam pengalaman klinisnya, Freud banyak berhadapan dengan orang-orang yang mengalami gangguan mental, khususnya gangguan kecemasan yang pada zaman itu disebut neurosis. Lebih jauh, Freud berusaha memahami pengalaman-pengalaman pasien-pasiennya di saat tidur dengan mendengarkan cerita mimpi mereka dan menginterpretasikan makna dari mimpi-mimpi itu.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup28
• Carl Gustav Jung juga dengan lebih jelas lagi menerapkan feno-menologi dalam memahami problem psikologis klien-kliennya. Dia menekankan pentingnya sikap mendengarkan, menyingkirkan rasa “sok tahu”, dan mengingatkan kita akan bahaya mengintervensi perjalanan hidup klien. Seperti Freud, Jung juga banyak bertemu dengan orang yang mengalami gangguan mental. Dia bahkan me-langkah lebih jauh dengan mengeksplorasi pengalaman orang-orang dalam beragam budaya.
• PsikologihumanistikCarlRogersdikenal jugadengan istilah lain“psikologi eksistensial-fenomenologis”. Psikologi humanistik atau psi kologi eksistensial-fenomenologis menekankan pentingnya men-dengarkan pengalaman hidup seseorang tanpa men-judge atau me-nilai. Istilah populernya nonjudgemental. Dari sikap nonjudge mental itu, muncul pemahaman akan pengalaman orang lain.
• Banyakpenelitidibidangpsikologitranspersonaljugamenggunakanstudi fenomenologis untuk memahami pengalaman spiritual. Feno-menologi bisa digunakan untuk meneliti pengalaman zikir, penga-laman meditasi, pengalaman yoga, pengalanan kontemplasi, penga-laman kesurupan, dan macam-macam pengalaman spiritual lain.
Begitulah, fenomenologi sebenarnya sudah akrab dengan psikologi sejak awal berdirinya psikologi modern di tahum 1879. Pada tahun 1970-an, Amedeo Giorgi, seorang psikolog yang awalnya berkecimpung di bidang psikologi eksperimental, melihat pentingnya fenomenologi dalam memahami perilaku manusia dan dia memelopori penelitian fenomenologis yang berbasis pada filsafat fenomenologis yang dikemukakan Edmund Husserl. Penelitian fenomenologis ini di kemudian hari dikenal sebagai penelitian fenomenologis deskriptif. Darren Langdridge (2007:55) menulis tentang pentingnya peran Giorgi bagi pengembangan awal penelitian fenomenologis dalam psikologi.
BAB I Pendekatan Fenomenologis dalam Penelitian Kualitatif 29
Teks Asli
This is the most traditional approach to phenomenological psychology. It emerged in the 1970s at Duquesne (pronounced ‘Du-kane’) University in the USA, with the work of Amedeo Giorgi, now at Saybrook Graduate School, USA, and colleagues, and, indeed, is sometimes called the Duquesne School empirical-structural phenomenology or Husserlian phenomenological psychology). It is the most classically Husserlian method (see Chapter 2), being focused on identifying the essence of the phenomenon …. There is not one single way of conducting descriptive phenomenological psychology, although the approach first advocated by Giorgi and colleagues remains dominant.
Transkreasi
(Fenomenologi deskriptif ) ini adalah pendekatan paling tradisional untuk penelitian fenomenologis yang berkembang dalam psikologi. Fenomenologi deskriptif muncul pada tahun 1970-an di Universitas Duquesne (dibaca du-kene) di Amerika Serikat, lewat kerja Amedeo Giorgi bersama rekan-rekannya … kadang-kadang fenomenologi deskriptif disebut juga “fenomenologi empiris-struktural Mazhab Duquesne [karena lahir di Universitas Duquesne]” atau “psikologi fenomenologis Husserlian [karena dikembangkan dari pemikiran Edmund Husserl, Bapak Fenomenologi]”. Fenomenologi deskriptif adalah metode Husserlian paling klasik yang difokuskan untuk mengidentifikasikan esensi (inti) dari fenomena …. Meskipun cara menjalankan penelitian fenomenologis deskriptif dalam psikologi bervariasi, pendekatan yang pertama kali dicanangkan oleh Giorgi dan rekan-rekannya tetap menjadi yang dominan.
Pada tahun 1990-an, Jonathan A. Smith, seorang psikolog yang berkecimpung di bidang psikologi kesehatan di Inggris, juga melihat pentingnya fenomenologi dalam memahami berbagai fenomena psikologis. Jonathan Smith kemudian meletakkan dasar untuk penelitian fenomenologis yang dikenal sebagai interpretative phenomenological analysis (IPA). Kutipan berikut memberi informasi tentang awal kemunculan IPA (Smith, Flowers, & Larkin, 2009:12).
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup30
Teks Asli
IPA has a short and a long history. Its first real mark came with the publication of Jonathan Smith’s (1996) paper dalam Psychology and Health which argued for an approach to psychology which was able to capture the experiential and qualitative, and which could still dialogue with mainstream psychology. An important aim at this point was to stake a claim for a qualitative approach centred in psychology, rather than importing one from different disciplines.
Transkreasi
IPA punya sejarah yang pendek dan juga sejarah yang panjang. Tanda pertama yang jelas dari kemunculan IPA adalah dipublikasikannya tulisan Jonathan Smith di tahun 1996 dalam jurnal Psychology and Health [tulisan itu berjudul Beyond the divide between cognition and discourse: Using interpretative phenomenological analysis in health psychology]. Dalam tulisan itu, Jonathan berargumen tentang perlunya pendekatan bagi psikologi yang
mampu menangkap yang eksperiensial dan yang kualitatif dan yang masih bisa berdialog dengan psikologi yang diterima luas (mainstream). Tujuan utamanya adalah mencanangkan pendekatan kualitatif yang berpusat pada psikologi dan tidak melulu mengimpor pendekatan kualitatif dari disiplin-disiplin lain.
Tergambar juga cukup jelas bahwa penelitian fenomenologis yang berkembang dalam psikologi tidak bisa dilepaskan dari filsafat fenomenologis dan kebutuhan psikologi untuk memiliki metode kualitatifnya sendiri. Meski demikian, buku ini tidak akan masuk ke dalam pembicaraan tentang fenomenologi yang terlalu filosofis. Dalam buku ini, saya ingin menjadi lebih praktis dengan mengedepankan penerapan fenomenologi dalam penelitian psikologis.
31
BAB II
Penelitian dan Peneliti Fenomenologis
Dalam pengantar singkat tentang penelitian fenomenologis pada Bab I, cukup jelas bahwa penelitian fenomenologis terkoneksi dengan fenomenologi (filsafat fenomenologis). Semakin kita mendalami penelitian fenomenologis, semakin kita menyadari peran penting filsafat fenomenologis. Bahkan, bisa dikatakan bahwa penelitian fenomenologis mengambil makanannya dari fisafat fenomenologis. Buku yang sedang Anda baca ini adalah buku tentang penerapan fenomenologi dalam penelitian psikologis. Bila Anda ingin mengetahui lebih jauh tentang filsafat yang ada di balik penelitian fenomenologis, Anda bisa membaca buku-buku fenomenologi (filsafat fenomenologis) yang banyak tersedia dalam bahasa Inggris. Anda juga bisa membaca buku “Fenomenologi: Filsafat untuk Riset Fenomenologis” yang saya tulis sebagai pendamping buku yang sedang Anda baca ini.
A. Tentang Fenomenologi
Saya berharap bahwa pemaparan pada Bab I sudah bisa sedikit memperjelas yang dimaksud dengan fenomena, fenomenologi (filsafat fenomenologis), dan penelitian fenomenologis. Dalam bab ini, kita masih akan memperdalam lagi pemahaman tentang fenomenologi dan mengajukan definisi fenomenologi yang bisa kita gunakan dalam menjalankan penelitian fenomenologis. Pada Bab I, saya menampilkan definisi fenomenologi dalam psikologi yang diambil dari situs Wikipedia. Definisi tersebut berbunyi sebagai berikut:
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup32
“Phenomenology is the study of subjecitve experience.” “Fenomenologi adalah penelitian tentang pengalaman subjektif.”
Kita sudah menerima definisi itu sebagai definisi populer. Sekarang, mari kita sambungkan definisi fenomenologi itu dengan beberapa definisi yang lebih formal. Dalam Kotak 2.1, kita bisa membaca tiga definisi fenomenologi.
Kotak 2.1 Definisi Fenomenologi
Penulis Definisi
Martin Packer (2007:152)
“Phenomenology is the reflective study of the essence of consciousness as experienced from the first-person point of view.”
Terjemahan: Fenomenologi adalah penelitian reflektif tentang esensi (inti) dari kesadaran yang dialami dari perspektif orang pertama.
Komentar: Packer mengemukakan bahwa definisinya itu sejalan dengan pandangan Husserl, peletak dasar fenomenologi. Perspektif orang pertama berarti perspektif aku/saya yang mengalami. Definisi ini cocok untuk dijadikan referensi dalam penelitian fenomenologis deskriptif.
David Woodruff Smith (2003:3)
“Phenomenology is the study of structures of consciousness as experienced from the first-person point of view.”
Terjemahan: Fenomenologi adalah penelitian tentang struktur-struktur kesadaran sebagaimana dialami dari sudut pandang orang pertama.
Komentar: Definisi ini juga dikembangkan dari definisi fenomenologi menurut Husserl dan juga cocok untuk penelitian fenomenologis deskriptif.
BAB II Penelitian dan Peneliti Fenomenologis 33
Jonathan A. Smith,
Paul Flowers, Michael Larkin (2009:11)
“Phenomenology is a philosophical approach to the study of experience ... the founding principle of phenomenological inquiry is that experience should be examined in the way that it occurs, and in its own terms.”
Terjemahan: Fenomenologi adalah pendekatan filosofis untuk penelitian tentang pengalaman … prinsip dasar dari penelitian fenomenologis adalah bahwa pengalaman harus diteliti dengan memperhatikan bagaimana pengalaman itu terjadi [dalam kehidupan seseorang] dan [dibicarakan] dalam istilah-istilah yang tidak dilepaskan dari pengalaman itu.
Komentar: Definisi ini dikemukakan oleh Jonathan A. Smith dan diikembangkan dari pandangan fenomenologis interpretatif filsuf fenomenologi Martin Heidegger. Smith sebagai peletak dasar IPA mengajukan definisi itu untuk diterapkan dalam riset IPA.
Ciri yang menyatukan dari ketiga definisi tersebut adalah penekanan pada pengalaman masing-masing orang, masing-masing pribadi, masing-masing aku. Karena penelitian fenomenologis menginduk pada fenomenologi yang dicanangkan Husserl, ada baiknya bila kita membedah sebentar definisi yang dikemukakan Martin Packer tersebut.
1. Penelitian Fenomenologis Adalah Penelitian Reflektif
Ini berarti bahwa peneliti fenomenologis dituntut untuk menjadi peneliti reflektif. Refleksi berasal dari istilah Latin reflectere yang berarti membungkuk, mirip dengan bahasa tubuh orang Jepang saat memberi hormat. Peneliti yang reflektif adalah peneliti yang berani melihat dirinya sendiri dengan rendah hati dan memperhatikan pikiran dan perasaan yang berfluktuasi dalam diri sendiri. Singkat kata, peneliti fenomenologis adalah peneliti yang punya komitmen untuk mengawasi dirinya sendiri. Mungkin muncul pertanyaan: Bukankah kita ingin meneliti orang lain? Mengapa malah repot mengawasi diri sendiri? Diri sendiri harus diawasi karena setiap kita adalah pribadi yang dibentuk oleh pengalaman hidup kita masing-masing. Setiap orang unik, spesial. Persis di sinilah masalah pokoknya.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup34
Saya rentan melihat pengalaman pribadi orang lain dengan memakai pengalaman pribadiku. Jika itu terjadi, pengalaman orang lain tidak tampil apa adanya, tetapi tampil menurut apa yang ada dalam pikiranku. Dengan kata lain, pengalaman orang lain rentan tercemar oleh pengalaman pribadiku. Untuk menghindari kontaminasi seperti itu, saya harus mengenali kecenderungan-kecenderungan dalam diri saya yang bisa menghalangi saya melihat pengalaman orang lain apa adanya.
Ada satu pengalaman pribadi yang relevan untuk saya ceritakan di sini. Ada seorang mahasiswi yang ingin melakukan penelitian fenomenologis tentang pengalaman (subjektif ) istri yang suaminya berselingkuh. Saya bolehkan. Saat pengumpulan data, terjadi peristiwa yang mengejutkan. Dalam suatu wawancara, suami partisipan/subjek penelitian datang dan terjadi pertengkaran antara partisipan dan suaminya. Di luar kendali, mahasiswi saya ikut marah dan meneriaki si suami. Dia lalu datang menemui saya dan memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan penelitiannya. Dalam perbincangan kami, terungkap bahwa dia terdorong untuk meneliti pengalaman istri yang suaminya berselingkuh karena ayahnya sendiri berselingkuh. Dia sedih melihat ibunya yang sakit hati dan ikut menyimpan marah pada ayahnya. Dalam kondisi seperti itu, dia punya agenda pribadi ingin memahami seperti apa perasaan ibunya lewat partisipannya. Nah, mahasiswi saya ini gagal melihat rasa marah dalam dirinya sehingga dia ikut memarahi suami partisipannya. Ini contoh ekstrem bahwa kegagalan melihat atau mengawasi diri sendiri berdampak pada kegagalan melihat orang lain apa adanya.
2. Dari Perspektif Orang Pertama
Dalam linguistik (ilmu bahasa), istilah “perspektif orang pertama” berarti “aku/saya”. Jika peneliti bisa menjaga dan mengawasi dirinya sendiri, maka pengalaman orang lain bisa dilihat apa adanya tanpa dicemari oleh pengalaman pribadi peneliti. Setiap orang punya pengalaman yang unik. Dalam menjalankan penelitian fenomenologis, peneliti membiarkan partisipan/subjeknya berbicara tentang dunia pengalamannya. Kita berharap, partisipan terbuka mengatakan, “Aku
BAB II Penelitian dan Peneliti Fenomenologis 35
merasa…”, “Aku sedih…”, “Saya takut…”, “Aku bingung…” dan seterusnya. Subjek berbicara dalam dunia pengalamannya dan dimengerti dalam dunia pengalamannya itu. Inilah yang dimaksud Husserl dengan istilah “perspektif orang pertama (Aku/saya yang mengalami)”.
3. Esensi dari Kesadaran yang Dialami
Inilah tujuan dari fenomenologi Husserl, yaitu melihat esensi dari pengalaman partisipan. Dalam bahasa Jerman, penglihatan akan esensi disebut Wesenschau. Kata Jerman schauen yang berarti melihat dan Wesen yang berarti inti/esensi/hakikat. Wesenschau adalah penglihatan yang jernih, penglihatan yang tidak lagi dikotori oleh prasangka/praduga/penilaian/spekulasi/kekhawatiran/kecemasan dan yang semacam itu. Bila diri sendiri bisa dilihat dan diperhatikan, pengalaman orang lain bisa dilihat jernih tanpa dicemari pengalaman pribadi peneliti. Dalam penglihatan yang jernih itu, pemahaman muncul secara alami. Inti dari pengalaman orang lain bisa ditangkap. Inilah yang dimaksud Husserl dengan istilah “esensi/inti dari kesadaran yang dialami oleh si aku”.
Kita bisa mengajukan dua definisi untuk penelitian fenomenologis (lihat Kotak 2.2) dengan memperhatikan definisi fenomenologi tersebut, sambil mengaitkannya dengan definisi populer fenomenologi dalam Wikipedia. Dua definisi itu hanya berbeda dalam formulasi saja.
Kotak 2.2 Definisi Penelitian Fenomenologis
Definisi 1 : Phenomenological research is the reflective study of participant’s subjective experience.
Penelitian fenomenologis adalah penelitian reflektif tentang pengalaman subjektif partisipan.
Definisi 2 : Phenomenological research is the reflective study of experience from the first person point of view.
Penelitian fenomenologis adalah penelitian reflektif tentang pengalaman partisipan dari perspektif orang pertama.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup36
Istilah “penelitian reflektif ” berarti peneliti menerima bahwa persepsinya tentang orang lain itu subjektif dan dia bersedia melihat subjektivitasnya itu dengan jujur; sementara “pengalaman subjektif partisipan/pengalaman partisipan dari perspektif orang pertama” berarti peneliti memberi kesempatan kepada partisipannya untuk mengekspresikan dengan bebas dunia pengalaman pribadinya. Dalam wawancara penelitian, pengalaman subjektif itu diekspresikan dengan menggunakan kata ganti orang pertama (saya/aku), seperti saya/aku merasa …, saya/aku percaya …, saya/aku bingung …, saya/aku sulit menerima … saya/aku ragu …, dan yang semacam itu. Oleh karena itu, semakin banyak ekspresi saya/aku dalam transkrip wawancara, semakin jelas pengalaman subjektif partisipan kita.
B. Tentang Fenomena
Judul penelitian fenomenologis selalu berangkat dari fenomena. Seperti yang sudah dibicarakan di bab sebelumnya, fenomena secara umum adalah apa saja yang muncul dalam kesadaran seseorang. Dalam kesadaran peneliti di bidang arsitek, bisa muncul macam-macam fenomena yang terkait dengan bangunan, seperti atap, fondasi, kolom bangunan, dan seterusnya. Dalam kesadaran peneliti di bidang kedokteran, bisa muncul macam-macam fenomena yang terkait dengan aktivitas tubuh manusia, seperti ginjal, jantung, otak, dan seterusnya. Dalam kesadaran peneliti di bidang psikologi, fenomena muncul sebagai peristiwa mental/kejadian mental/aktivitas mental dalam pengalaman hidup seseorang. Untuk memperjelas yang dimaksud dengan fenomena dalam psikologi, mari kita berlatih lewat pertanyaan-pertanyaan berikut.
1. Fenomena (peristiwa/kejadian/aktivitas mental) apa yang muncul dalam kesadaran wanita yang mengalami perceraian?
2. Fenomena (peristiwa/kejadian/aktivitas mental) apa saja yang mun-cul dalam kesadaran ibu yang mengalami memiliki anak autis?
3. Fenomena (peristiwa/kejadian/aktivitas mental) apa saja yang mun-cul dalam kesadaran orang yang pertama kali mengalami ibadah haji?
4. Fenomena (peristiwa/kejadian/aktivitas mental) apa yang muncul dalam kesadaran mahasiswa yang mengalami kuliah di jurusan
BAB II Penelitian dan Peneliti Fenomenologis 37
tertentu bukan karena kemauaunnya, tetapi karena kemauan orang tuanya?
5. Fenomena (peristiwa/kejadian/aktivitas mental) apa yang muncul dalam kesadaran remaja yang mengalami kecanduan alkohol?
Fenomena itu akan terlihat lebih jelas bila kita berbicara langsung dengan orang-orang yang mengalami langsung fenomena itu. Semua pertanyaan tersebut bisa menjadi titik awal dalam membuat judul penelitian fenomenologis. Kelima pertanyaan tersebut bisa kita transformasikan men-jadi judul penelitian berikut.
Penelitian fenomenologis tentang pengalaman wanita pasca-perceraian.Studi fenomenologis tentang pengalaman ibu yang memiliki anak
autis.Kajian fenomenologis tentang pengalaman pertama menunaikan
ibadah haji.Eksplorasi fenomenologis tentang pengalaman mahasiswa mengikuti
kemauan orang tua kuliah di jurusan tertentu.Investigasi fenomenologis tentang pengalaman remaja yang kecan-
duan alkohol.
Kesan yang muncul dari contoh-contoh tersebut adalah bahwa membuat judul penelitian fenomenologis ternyata sangat mudah. Kenyataannya memang begitu. Judul penelitian fenomenologis sebanyak pengalaman manusia dalam menjalani hidupnya. Meski demikian, peneliti selalu perlu mempertimbangkan manfaat dari penelitiannya bagi disiplin ilmu yang sedang dia digeluti. Ketika menemukan fenomena untuk diteliti, pertanyaan yang mendesak untuk dijawab adalah: Manfaat apa yang bisa didapatkan dari fenomena ini bagi ilmu yang sedang saya pelajari? Selain memikirkan kebermanfaaatan, peneliti juga perlu mempertimbangkan dua poin berikut.
1. Aksesibilitas
Apakah peneliti punya akses untuk menemui dan menggali pengalaman subjek? Judul yang menarik belum cukup. Peneliti perlu memikirkan situasi lapangan sejak awal. Apakah calon subjek/partisipan bersedia? Bila calon partisipan bersedia, itu juga belum cukup. Apakah
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup38
subjeknya benar-benar mau terbuka memberi informasi? Kebersediaan subjek dan keterbukaan subjek itulah yang disebut aksesibilitas. Subjek yang bersedia dan terbuka adalah subjek yang bisa diakses.
2. Homogenitas Subjek
Apakah semua partisipan yang akan ditemui memiliki ciri-ciri pengalaman yang sama? Bila peneliti tertarik dengan penderita bipolar, apakah semua calon partisipan sudah dicek sebagai orang-orang yang memang didiagnosis mengalami gangguan bipolar (bipolar disorder)? Untuk sekadar diketahui bahwa gangguan bipolar adalah gangguan psikologis yang secara umum dicirikan dengan ayunan suasana hati yang ekstrem dari girang ke depresi. Jika tidak semua partisipan didiagnosis bipolar, maka partisipan penelitian tidak homogen. Kalau semua bipolar, partisipan penelitian homogen. Kata homos dalam bahasa Yunani berarti “sama” dan kata genos berarti “jenis”. Homogen berarti berjenis sama. Lawan kata homos adalah heteros yang berarti “lain atau berbeda”. Nah, carilah subjek yang homogen, bukan yang heterogen.
Misalnya kita ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengalaman cuci darah pada pasien sakit ginjal”. Kita ingin memahami artinya cuci darah bagi pasien-pasien sakit ginjal yang menjadi partisipan dalam penelitian kita. Judul yang terkesan bagus dan bermanfaat. Sekarang, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut.
1. Kebermanfaatan : Apa manfaat penelitian ini bagi disiplin ilmu yang saya tekuni?
2. Aksesibilitas : Apakah calon-calon partisipan saya bersedia atau membuka diri untuk diwawancarai?
3. Homogenitas : Apakah semua calon partisipanku sudah menja-lani cuci darah lebih dari setahun?
Satu contoh lagi. Seorang peneliti ingin memahami “Pengalaman Biksu dalam Mempraktikkan Mindfulness (Latihan Berkesadaran Penuh)”. Judul yang terkesan bagus dan bermanfaat. Sekarang, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut.
BAB II Penelitian dan Peneliti Fenomenologis 39
1. Kebermanfaatan : Apa manfaat penelitian ini bagi disiplin ilmu yang saya tekuni?
2. Aksesibilitas : Apakah biksu-biksu yang akan saya temui ber-sedia dan terbuka untuk diwawancarai?
3. Homogenitas : Apakah semua partisipanku memang adalah biksu, bukan samanera (calon biksu)?
C. Kualitas Peneliti Fenomenologis
Meskipun menemukan judul penelitian fenomenologis terkesan gampang, tetapi menjadi peneliti fenomenologis butuh komitmen dan keseriusan. Ada kualitas-kualitas yang harus dimiliki oleh peneliti fenomenologis. Dalam pengalaman saya menjalankan penelitian fenomenologis dan membimbing penelitian fenomenologis, saya menemukan bahwa seorang peneliti fenomenologis sebaiknya memiliki kualitas berikut.
1. Peneliti Bisa Menerima bahwa Persepsi itu Relatif
Di salah satu ruangan di sebuah universitas, saya membaca tulisan “Ruang Penyamaan Persepsi”. Saya kaget, “Lho kok persepsi bisa sama?”, persepsi itu tergantung pada pengalaman masing-masing orang. Jika seratus orang menonton konser musik yang sama, apakah persepsi mereka sama? Tentu saja tidak. Mereka yang tahu betul musik punya persepsi yang berbeda dengan orang yang tahu sedikit tentang musik. Orang yang tahu sedikit itu pun berbeda kadar sedikitnya, tergantung musik apa yang mengisi hidupnya. Karena itu, peneliti fenomenologis harus berhati-hati dalam memahami persepsi partisipan/subjek dalam penelitiannya. Kita perlu berhati-hati agar tidak mengotori pengalaman subjek dengan pengalaman kita. Biarkan subjek melihat pengalamannya menurut persepsinya. Dalam fenomenologi, pembicaraan tentang persepsi sering kali dikaitkan dengan apa yang dalam bahasa Jerman disebut Abschattung. Abschattung berarti “aspek” atau “faset (bagian)” atau “sudut pandang”. Ketika kita melihat sesuatu, kita tidak pernah bisa melihatnya secara utuh karena kita hanya bisa melihat sesuatu itu dari Abschattung (sudut pandang) tertentu. Ini mirip dengan fotografer yang memotret suatu gedung. Dalam sekali jepretan, dia tidak mungkin bisa memotret semua sudut pandang dari gedung itu. Jika si pemotret
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup40
mengelilingi gedung sambil memotretnya, maka dia bisa mendapatkan beberapa Abschattung (sudut pandang) dari gedung itu. Bagaimanapun, sisi dalam dari gedung itu belum terjangkau.
Apa relevansi Abschattung ini bagi peneliti fenomenologis? Dalam upaya memahami pengalaman partisipan, peneliti mewawancarai partisipan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar bisa melihat “bangunan” pengalaman partisipan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan diharapkan bisa memberi gambaran tentang pengalaman partisipan dari beberapa Abschattung. Setelah wawancara, kita mendapatkan hasil pemotretan bangunan pengalaman dalam bentuk transkrip wawancara. Lewat transkrip inilah, peneliti berusaha memahami pengalaman partisipannya. Peneliti ingin masuk ke dalam “bangunan pengalaman” partisipan. Pengalaman itu subjektif dan perlu dimengerti dari dalam subjektivitas yang mengalaminya. Melihat rumah dan mengalami rumah itu berbeda. Mengalami rumah berarti memberi makna subjektif untuk rumah. Saya perlu mendengarkan pengalaman Anda dalam rumah agar saya bisa paham makna subjektif rumah bagi Anda. Memiliki ayah dan mengalami ayah itu berbeda. Saya perlu mendengarkan pengalaman interaksi Anda dengan ayah Anda agar saya bisa paham makna subjektif ayah bagi Anda.
Untuk itu, peneliti perlu merenungkan arti atau makna (psikologis) dari semua Abschattung dalam persepsi partisipan. Jika permenungan bisa dijalankan secara ketat (rigorous) atau ilmiah (scientific), peneliti tidak hanya mendapatkan arti atau makna, tetapi juga inti dari pengalaman partisipan. Permenungan yang ketat (rigorous)? Iya, fenomenologi memang ingin menjadikan permenungan (refleksi) sebagai metode penelitian yang ketat sehingga dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Poin kedua berikut akan memperjelasnya.
2. Peneliti Bisa Menjalankan Epochē
Untuk bisa melihat inti dari pengalaman partisipan, peneliti perlu menjalankan epochē. Istilah epochē ini adalah istilah sentral dalam fenomenologi, khususnya dalam fenomenologi Edmund Husserl. Husserl mengambil istilah itu dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Jerman, epochē diterjemahkan Einklämmerung dan dalam bahasa Inggris
BAB II Penelitian dan Peneliti Fenomenologis 41
umumnya diterjemahkan bracketing. Baik Einklämmerung maupun bracketing berarti upaya memasukkan dalam kurung (dikurung). Sampai di sini, kita perjelas dahulu istilah penting berikut ini.
epochē = Einklämmerung = bracketing = upaya mengurung
Apa yang dikurung? Yang dikurung adalah pengetahuan yang sudah bercokol dalam diri peneliti, yang potensial mengganggu dalam melihat pengalaman orang lain apa adanya. Kita cukup sering melihat orang lain menurut apa yang ada dalam pikiran kita/asumsi kita/kecurigaan kita/dugaan kita/anggapan kita/penilaian kita. Semua itu dikurung/disingkirkan sehingga kita bisa melihat keaslian/orisinalitas pengalaman orang lain. Epochē/Einklämmerung/bracketing ini adalah kerepotan utama seorang peneliti fenomenologis. Dengan menjalankan epochē, peneliti berkomitmen melihat orang lain apa adanya tanpa terdistorsi oleh asumsi/anggapan/penilaian/spekulasi/teori.
Dalam psikologi, epochē/Einklämmerung/bracketing ini disebut sikap tanpa penilaian (nonjudgemental attitude). Peneliti perlu berlatih atau, paling tidak, punya komitmen untuk menjalankan epochē itu dalam penelitiannya. Dalam beberapa literatur penelitian kualitatif, epochē itu dibicarakan secara dangkal sebagai membuang atau menyingkirkan teori. Pemahaman seperti itu muncul karena epochē dilepaskan dari fenomenologi. Pernyataan Lea Tufford dan Peter Newman (2010) berikut ini perlu menjadi perhatian kita.
Teks Asli
Bracketing is a method used in qualitative research to mitigate the potentially deleterious effects of preconceptions that may taint the research process. However, the processes through which bracketing takes place are poorly understood, in part as a result of a shift away from its phenomenological origins.
Transkreasi
Bracketing (epochē) adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif un-tuk mengurangi efek prakonsepsi (konsep-konsep yang sudah ada dalam diri pene liti) yang potensial merusak, yang bisa mengo-tori proses penelitian. Sayangnya, proses menjalankan epochē kurang dimengerti dengan baik. Kurangnya pemahaman itu sebagian disebabkan oleh dijauhkannya epochē dari sumbernya, yaitu fenomenologi.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup42
3. Peneliti Memiliki Kemampuan Mendengarkan
Latihan yang paling bagus untuk mengembangkan epochē adalah berlatih mendengarkan orang lain. Saat orang lain bercerita, kita benar-benar mengarahkan diri pada orang itu, benar-benar melepaskan macam-macam pikiran dalam diri kita sendiri. Saya kira, seorang psikolog juga harus memiliki kemampuan ini agar tidak keliru dalam memahami problem psikologis klien-kliennya. Cukup diingat bahwa mendengarkan (listening) tidak sama dengan mendengar (hearing). Listening berarti membuka diri selebar-lebarnya dan membiarkan orang lain menampilkan diri dengan pengalaman hidupnya.
4. Peneliti Bisa Menjalankan Empati
Orang yang bisa mempraktikkan epochē (bracketing/mengurung) dan bisa mendengarkan orang lain adalah orang-orang yang secara alamiah mengembangkan kemampuan empati. Apakah empati itu? Istilah empati dalam bahasa Indonesia adalah serapan dari kata Inggris empathy. Istilah empathy menjadi bagian dari bahasa Inggris setelah Edward Titchener menerjemahkannya kata Jerman Einfühlung menjadi empathy pada tahun 1909. Sebenarnya, istilah empati kurang begitu pas. Empathy dalam bahasa Inggris berasal dari kata Yunani empatheia yang merupakan gabungan dari em (dalam)+pathos (derita/rasa susah) sehingga empati pada dasarnya berarti merasakan derita orang lain dari dalam. Kata Jerman Einfühlung berarti one-feeling dalam bahasa Inggris atau satu rasa dalam bahasa Indonesia. Einfühlung (one-feeling/satu rasa) adalah kapasitas yang membuat kita mampu membuka diri agar terhubung dengan perasaan orang lain. Kita tidak dilahirkan dengan kemampuan Einfühlung atau empati itu. Empati adalah proses alami yang muncul di saat kita bisa mengarahkan diri sepenuhnya pada orang lain yang sedang menceritakan pengalaman hidupnya. Kemampuan menjalankan empati terkait dengan kemampuan mendengarkan.
Empat hal itu bisa dijadikan sebagai empat prasyarat menjadi seorang peneliti fenomenologis. Siapa saja yang bisa mempraktikkannya dalam proses penelitian, saya kira dia tidak akan kesulitan menjalankan penelitian
BAB II Penelitian dan Peneliti Fenomenologis 43
fenomenologis. Kita tidak harus berhasil mempraktikkan semua itu terlebih dahulu untuk bisa menjadi peneliti fenomenologis. Mempraktikkan empat poin tersebut adalah tantangan yang menggairahkan bagi siapa saja yang ingin menjadi psikolog. Buah yang bisa diharapkan dari empati adalah munculnya pemahaman tentang pengalaman orang lain.
45
BAB III
Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): Pengantar Singkat dan Formulasi Judul
Saat membicarakan pendekatan fenomenologis pada Bab I, kita berkenalan sekilas dengan dua versi penelitian fenomenologis yang ber-kembang dalam psikologi, yaitu (1) penelitian fenomenologis interpretatif dan (2) penelitian fenomenologis deskriptif. Dalam bab ini, pembicaraan kita akan fokus pada penelitian fenomenologis interpretatif yang banyak digunakan dalam karya ilmiah, yaitu interpretative phenomenological analysis (IPA). Sebenarnya, kita bisa saja mengindonesiakan interpretative pheno-menological analysis menjadi “analisis fenomenologis interpretatif ” dan me-nyingkatnya menjadi AFI, namun akronim IPA sudah dikenal sangat luas di kalangan peneliti fenomenologis di banyak negara. Oleh karena itu, disarankan untuk tetap menggunakan istilah Inggrisnya agar komunikasi di antara peneliti-peneliti lintasnegara menjadi lebih mudah terjalin. Nah, mari kita lihat lebih dekat yang dimaksud dengan IPA.
A. Interpretative Phenomenological Analysis (IPA)
Sebelum membicarakan lebih jauh tentang IPA itu, saya ingin mengulangi dulu pernyataan penting di bab sebelumnya, yaitu penelitian fenomenologis sebagai penelitian yang berfokus pada pengalaman subjektif. Sasaran kita adalah cerita subjektif dari orang yang mengalami langsung suatu fenomena. Karena itu, penelitian fenomenologis cukup sering juga disebut sebagai penelitian yang mengandalkan perspektif orang pertama
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup46
(first-person perspective). Perspektif orang pertama berarti perspektif dari sudut pandang si aku/saya yang mengalami.
Oleh karena itu dalam wawancara penelitian, partisipan seharusnya ba-nyak mengungkapkan pikiran, perasaan, sikap, atau kepercayaan pribadinya sebagai orang yang mengalami langsung. Terkait dengan itu, IPA sebagai penelitian fenomenologis berfokus pada kesibukan berikut.
Peneliti ingin menafsirkan bagaimana partisipan sebagai orang yang mengalami langsung peristiwa tertentu menafsirkan penga-lamannya.
Hafalkan dahulu pernyataan tersebut. Tunda dahulu melanjutkan membaca tulisan ini sebelum menghafal pernyataan tersebut. Dalam pernyataan itu, ada dua proses “penafsiran/interpretasi”, yaitu (1) penafsiran oleh par tisi pan dan (2) penafsiran oleh peneliti. Kata kunci dalam IPA adalah “penafsiran” itu. Istilah lain untuk penafsiran itu adalah “interpretasi” dan “her meneutika”. Istilah “hermeneutika” lebih sering ditemui dalam filsafat. Menafsirkan adalah aktivitas utama dalam IPA sehingga peneliti dituntut untuk mengembangkan kemampuan menafsirkan. Muara atau hasil dari penaf siran peneliti adalah pemahaman akan makna yang diberikan oleh partisipan untuk pengalaman hidupnya. Mengapa penafsiran/interpretasi/hermeneutika itu dijadikan aktivitas utama? Perhatikan urutan berikut.
1. Saat seseorang bercerita tentang pengalamannya, dia sebenarnya sedang menafsirkan pengalamannya itu. Saya, misalnya, bercerita ten tang pengalamanku menjalankan terapi dengan hipnosis. Itu ber-arti bahwa saat saya bercerita, saya sedang menafsirkan peristiwa-peristiwa dalam hidupku yang berhubungan dengan pengalaman saya menjalankan terapi dengan hipnosis.
2. Lalu datang peneliti yang mendengarkan pengalaman saya sebagai orang yang menjalankan terapi dengan hipnosis.
3. Omongan saya lalu direkam dan ditranskripsikan.
4. Setelah menjadi transkrip, omongan saya dibaca dan mulai ditaf-sirkan.
BAB III Interpretative Phenomenological Analysis (IPA):Pengantar Singkat dan Formulasi Judul 47
5. Harapan peneliti: dari penafsiran/interpretasinya itu muncul pema-haman tentang apa artinya menjalankan terapi dengan hipnosis bagi saya.
Cukup jelas sekarang yang sebenarnya terjadi pada seorang peneliti fenomenologis dengan IPA. Pemahaman peneliti IPA tentang pengalaman partisipan keluar dari penafsirannya terhadap penafsiran partisipan. Sekarang, perhatikan lagi pernyataan berikut.
Dalam IPA, subjek/partisipan penelitian melakukan penafsiran untuk pengalamannya sendiri saat bercerita. Kemudian, datang seorang peneliti fenomenologis yang menggunakan IPA. Dia mewawancarai partisipan dan kemudian membuat transkrip. Saat menganalisis transkrip, peneliti IPA menafsirkan penafsiran subjek.
Jadi, ada dua aktivitas penafsiran/interpretasi dalam IPA: satu tafsir berasal dari subjek dan satunya lagi berasal dari peneliti. IPA mengakui adanya dua tafsiran itu. Dalam IPA, kita menyebutnya double-hermeneutic (penafsiran ganda), yaitu penafsiran/interpretasi peneliti terhadap penafsiran/interpretasi partisipan.
B. Tiga Pilar IPA
Penelitian fenomenologis adalah penelitian tentang pengalaman manusia. Dalam upaya memahami pengalaman manusia, IPA bersandar pada tiga pilar, yaitu (1) fenomenologi (filsafat fenomenologis), (2) hermeneutika (teori tentang penafsiran/interpretasi), dan (3) idiografi (kajian tentang manusia dalam keunikannya). Ketiga pilar itu akan lebih baik dibicarakan bila kita langsung mengaitkannya dengan pemikiran dari beberapa filsuf kunci dalam fenomenologi.
1. Fenomenologi
Fenomenologi adalah filsafat yang secara eksplisit menekankan pentingnya meneliti pengalaman langsung (lived experience). Kemunculan fenomenologi tidak bisa dilepaskan dari pakar matematika dan logika Edmund Husserl yang mencanangkan filsafat yang bertujuan meneliti
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup48
pengalaman manusia secara ketat dan ilmiah. Husserl ingin agar pengalaman manusia dimengerti dalam keasliannya. Berikut semboyan yang dikumandangkan Husserl.
Zurück zu den Sachen selbst! Back to the things themselves!
Kembali ke fakta-fakta (fenomena-fenomena) itu sendiri!
Dalam penelitian fenomenologis, kembali ke fakta-fakta (fenomena-fenomena) berarti bahwa peneliti mau melihat pengalaman partisipan/subjek tanpa dikendalikan oleh pandangan-pandangan teoretis tertentu, apalagi asumsi-asumsi. Peneliti fenomenologis ingin melihat pengalaman partisipan dengan jernih. Caranya adalah dengan menjalankan yang dalam bahasa Yunani di sebut epochē, yaitu menyingkirkan prasangka, prapemikiran, praduga, asumsi, atau spekulasi dalam diri peneliti. Peneliti yang memiliki penglihatan yang jernih akan mampu melihat inti dari pengalaman partisipan. Dalam bahasa Yunani, inti itu disebut eidos. Peneliti fenomenologis ingin menemukan eidos dari pengalaman partisipan. Pandangan Husserl ini menjadi referensi induk penelitian fenomenologis deskriptif (PFD).
Interpretative phenomenological analysis (IPA) atau analisis feno-me nologis interpretatif tidak mengikuti pandangan Husserl itu, tetapi mengikuti pandangan Martin Heidegger, filsuf fenomenologi yang sebe narnya adalah murid Husserl. Dalam bahasa Jerman, Heidegger menyebut manusia sebagai Dasein (dibaca dasain). Dasein berasal dari dua kata, yaitu da (di sana) dan sein (ada). Jadi secara harfiah, Dasein berarti ada-di-sana. Jika kata Jerman itu ingin dipaksakan menjadi bahasa Indonesia, maka akan terasa janggal. Oleh karena itu, kita tidak perlu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Cukup diketahui bahwa Heidegger memunculkan istilah Dasein ini untuk membicarakan manusia yang “terlempar (geworfen)”. Ya, manusia adalah makhluk yang terlempar ke dalam dunia.
Sebagai makhluk yang terlempar ke dalam dunia, manusia tiba-tiba saja sudah menemukan dirinya dalam dunia. Manusia pada dasarnya tidak tahu dia dari mana dan mau ke mana. Dia tidak paham
BAB III Interpretative Phenomenological Analysis (IPA):Pengantar Singkat dan Formulasi Judul 49
siapa dirinya dirinya dan karena itu, dia berusaha paham siapa dirinya. Kenyataan yang dia ketahui adalah bahwa dia sudah menemukan dirinya berada-dalam-dunia bersama benda-benda, orang lain, dan makhluk lain. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, “Sebagai makhluk yang terlempar, bagaimana atau dengan cara apa manusia memahami pengalaman hidupnya?”
Dalam upaya memahami pengalaman hidupnya, manusia memberi makna pada macam-macam peristiwa yang terjadi dalam hidupnya itu. Upaya memberi makna pada dasarnya adalah penafsiran (inter-pretasi). Oleh karena itu, penafsiran adalah aktivitas utama kita dalam menemui berbagai peristiwa hidup. IPA adalah jalan memahami bagaimana manusia menafsirkan pengalaman hidupnya.
Selain Husserl dan Heidegger, masih ada filsuf-filsuf lain yang punya peranan penting bagi perkembangan fenomenologi. Beberapa di antara mereka yang terkenal adalah filsuf Prancis penerima hadiah nobel bidang sastra Jean-paul Sartre, Maurice-merleau Ponty, atau Paul Ricoeur. Di sini, saya tidak menyediakan tempat untuk membicarakan pemikiran mereka satu per satu. Bagi pembaca yang ingin memahami lebih jauh pandangan filsuf-filsuf fenomenologi, saya menyarankan membaca buku saya yang lain yang berjudul Fenomenologi: Filsafat untuk Riset Fenomenologis.
2. Hermeneutika
Untuk memahami dasar hermeneutika dalam IPA, ada tiga tokoh penting yang kerap disebut yaitu Friedrich Schleiermacher, Martin Heidegger, dan Hans-Georg Gadamer. Kita mulai dengan Schleier-macher. Dalam hermeneutika versi Schleiermacher, interpretasi atau penafsiran dibagi menjadi dua: (1) interpretasi gramatikal dan (2) interpretasi psikologis. Interpretasi gramatikal adalah interpretasi teks secara objektif; sedangkan interpretasi psikologis adalah interpretasi teks secara subjektif. Jika saya mengatakan, “Saya senang di rumah.” Bagaimana Anda menginterpretasikan ucapan saya itu? Anda bisa memperhatikan susunan kalimatnya dan membuka kamus untuk menemukan makna
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup50
kata “saya”, “senang”, dan “rumah”. Itu adalah penafsiran gramatikal. Dalam penafsiran psikologis, Anda masuk ke dalam suasana psikologis dari rumah yang ada dalam pengalaman pribadi saya (apa artinya rumah bagi saya?) dan memahami bagaimana suasana psikologis dalam rumah itu bisa menimbulkan rasa senang. Apa yang saya dan Anda rasakan dan pikirkan tentang rumah tentu saja subjektif. Karena Anda ingin memahami saya, maka Anda perlu masuk ke perasaan dan pikiran saya tentang rumah.
Proses penafsiran dalam IPA juga terhubung cukup kuat dengan pandangan Martin Heidegger, tokoh fenomenologi yang baru saja kita bicarakan. Dalam fenomenologi Heidegger, interpretasi adalah tema yang dominan. Bagaimana Heidegger menghubungkan fenomenologi dan interpretasi? Begini, fenomenologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu phainomenon yang berarti penampakan dan logos yang berarti analisis atau kajian. Fenomenologi berarti analisis atau kajian tentang fenomena (penampakan sesuatu). Di bab sebelumnya, kita sudah membicarakan apa itu fenomena dalam psikologi. Berikut ini rekomendasi untuk mendefinisikan “fenomena”.
Fenomena adalah peristiwa/kejadian/aktivitas mental yang tampak/muncul dalam kesadaran seseorang.
Fenomenologi adalah analisis terhadap peristiwa/kejadian/aktivitas mental. Untuk melakukan analisis terhadap fenomena, Husserl meminta kita melakukan epochē. Heidegger tidak sepakat dengan pandangan Husserl itu. Bagi Heidegger, setiap orang mengalami fenomena dan memberi makna untuk fenomena yang dialaminya itu. Singkat kata, setiap orang adalah penafsir untuk fenomena yang dialaminya.
Dalam IPA, peneliti ingin memahami bagaimana partisipan menaf-sirkan fenomena yang dialaminya. Peneliti punya pikiran dan perasaannya sendiri dan partisipan punya pikiran dan perasaannya sendiri. Suasananya menjadi sedikit runyam di sini. Pikiran dan perasaan peneliti bertemu dengan pikiran dan perasaan partisipannya. Dalam pertemuan itu, peneliti perlu jujur melihat pikiran dan perasaannya sendiri. Di sepanjang penelitian, saya sebagai peneliti terus-menerus merevisi diri saya sampai
BAB III Interpretative Phenomenological Analysis (IPA):Pengantar Singkat dan Formulasi Judul 51
muncul pemahaman yang jernih tentang pengalaman partisipan saya. Dalam cara itulah, penafsiran kita menjadi semakin dalam dan semakin tajam. Dalam cara itulah, epochē berjalan dalam IPA.
Masih ada satu tokoh lagi yang juga penting dalam hermeneutika, yaitu Hans-Georg Gadamer. Pandangan Gadamer bisa dikatakan sebagai pengembangan dari pandangan Heidegger. Intinya, peneliti tidak bisa dipisahkan dari partisipannya. Bila partisipan saya adalah seorang wanita transgender, maka pengetahuan tentang transgender yang sudah bercokol dalam diri saya bisa memengaruhi saya. Partisipan punya pandangan-nya tentang transgender dan saya punya pandangan-ku tentang transgender. Perbedaan itu alami. Saya hanya perlu mempertemukan pandangan saya dengan padangan partisipan saya. Pertemuan pandangan saya dan parti si pan saya disebut penyatuan horizon (fusion of horizons). Dalam penya tuan horizon itu, saya membandingkan pandanganku dan pan-dangan partisipanku. Saya melihat perbedaan antara pandanganku dan partisipanku, dan saya merevisi pandanganku tentang pandangan parti-sipanku. Kejujuran diri dan kesadaran peneliti mengenai pandangan-pan dangannya sendiri akan membantunya melihat dengan jernih pengalaman partisipan.
3. Idiografi
Pilar yang terakhir adalah idiografi. Pilar idografi di sini bisa diartikan sebagai pengakuan bahwa setiap orang unik dan khas dalam caranya memaknai berbagai fenomena yang terjadi dalam hidupnya. Kata Yunani “idios” berarti pribadi atau unik dan “graphein” berarti menulis atau menggambar. Idiografi adalah penggambaran atau penulisan sesuatu yang pribadi dan unik. IPA benar-benar memperhatikan sesuatu yang pribadi dan unik dalam pengalaman partisipan. Pengalaman pribadi partisipan dianalisis secara rinci. Pengalaman Lia adalah pengalaman Lia dalam dunia kehidupannya. Pengalaman Hans adalah pengalaman Hans dalam dunia kehidupannya. Setiap partisipan dimengerti dalam konteks kehidupannya masing-masing. Singkat kata, setiap orang dilihat sebagai kasus unik. Jika Anda meneliti tiga subjek, maka IPA menuntut agar peneliti menganalisis subjek masing-masing secara terpisah tanpa memaksakan pengalaman satu subjek ke subjek lain. Oleh karena itu,
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup52
IPA tidak mempermasalahkan jumlah sampel yang kecil, bahkan analisis satu partisipan dengan pengalaman yang langka dan menarik juga bukan masalah.
Bila ada fenomena yang umum di antara partisipan, apakah fenomena yang umum itu diabaikan? Pengalaman manusia yang satu dengan yang lain bisa terhubung sehingga wajar bila ada kemiripan. Boleh saja ada kemiripan antarpartisipan. Meski demikian, kemiripan itu tidak dikaitkan dengan generalisasi atau upaya menemukan prinsip umum yang berlaku untuk semua. Fenomenologi tidak mengenal generalisasi. IPA fokus pada yang khas dan yang unik, tetapi juga menerima bahwa beberapa partisipan bisa menunjukkan kemiripan dalam kekhasan mereka. Dalam IPA, tidak ada pertentangan antara yang khas/unik (particular) dan yang umum (general). Jika Anda masuk begitu dalam ke pengalaman pribadi dan unik seseorang, ada peluang bagi Anda untuk menemukan yang umum lewat pengalaman yang unik dan pribadi itu.
C. Perumusan Judul Penelitian dengan IPA
Fomulasi atau perumusan judul adalah langkah paling awal dalam memantapkan diri menjalankan penelitian fenomenologis. Cara merumuskan judul dalam IPA memang cukup bervariasi, tetapi ada rumusan-rumusan judul yang umum kita temui. Bunyi rumusan judul yang umum itu kita sebut bunyi judul generik. Berikut ini adalah beberapa contoh cara merumuskan judul. Anggaplah, kita melihat seorang ibu yang mengasuh anak yang secara biologis bukan anaknya. Kita lalu tertarik untuk meneliti pengalaman mengasuh itu. Dalam Kotak 3.1, Anda bisa membaca beberapa contoh cara merumuskan judul dalam penelitian IPA.
BAB III Interpretative Phenomenological Analysis (IPA):Pengantar Singkat dan Formulasi Judul 53
Kotak 3.1 Contoh-contoh Formulasi Judul dalam Penelitian IPA
1. Pengalaman menjadi ibu asuh.
• Interpretative phenomenological analysis tentang pengalaman menjadi ibu asuh.• Analisisfenomenologisinterpretatiftentangpengalamanmenjadiibuasuh.• Pengalaman menjadi ibu asuh: (sebuah) interpretative phenomenological analysis.• Pengalamanmenjadiibuasuh:(sebuah)analisisfenomenologisinterpretatif.
Komentar: Formulasi judul ini berasal dari pandangan bahwa fenomenologi adalah kajian tentang pengalaman manusia. Istilah “sebuah” boleh dihilangkan sehingga saya memasukkannya dalam kurung. Bahasa Indonesia sebenarnya tidak mengenal kata sandang “sebuah/suatu”. Kata sandang itu menjadi bagian dalam bahasa Indonesia karena penyerapan dari bahasa Belanda “een” dan bahasa Inggris “a/an”.
2. Makna menjadi ibu asuh.
• Interpretativephenomenologicalanalysis tentang makna menjadi ibu asuh.• Analisisfenomenologisinterpretatiftentangmaknamenjadiibuasuh.• Maknamenjadiibuasuh:(sebuah)interpretative phenomenological analysis.• Maknamenjadiibuasuh:(sebuah)analisisfenomenologisinterpretatif.
Komentar: Formulasi judul ini berasal dari pandangan bahwa orang yang mengalami sesuatu akan memberi makna untuk sesuatu yang dialaminya itu. Makna di sini adalah peristiwa subjektif yang muncul saat seseorang mengalami sesuatu. Saat seseorang mengalami tidak lulus ujian, dia secara subjektif memberi makna untuk ketidaklulusannya itu. Tidak mungkin ketidaklulusan itu tanpa makna pribadi. Begitu juga dengan ibu yang mengadopsi anak. Pengalamannya mengadopsi anak pasti memiliki makna pribadi.
3. Bagaimana ibu memaknai pengalamannya mengasuh anak?
• Interpretativephenomenologicalanalysis tentang bagaimana ibu memaknai pengalamannya mengasuh anak.
• Analisisfenomenologisinterpretatiftentangbagaimanaibumemaknaipengalamannya mengasuh anak.
• Bagaimanaibumemaknaipengalamannyamengasuhanak?(Sebuah)interpretative phenomenological analysis.
• Bagaimanaibumemaknaipengalamannyamengasuhanak?(Sebuah)analisisfenomenologis interpretatif.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup54
Komentar: Formulasi judul ini sama dengan formulasi nomor 2 di atas. Kita hanya merumuskannya dalam kalimat tanya.
4. Apa artinya menjadi ibu asuh?
• Interpretativephenomenologicalanalysis tentang apa artinya menjadi ibu asuh.• Analisisfenomenologisinterpretatiftentangapaartinyamenjadiibuasuh.• Apaartinyamenjadiibuasuh?(Sebuah)interpretative phenomenological
analysis.• Apaartinyamenjadiibuasuh?(Sebuah)analisisfenomenologisinterpretatif.
Komentar: Formulasi judul ini sama dengan formulasi nomor 2 dan 3 di atas. Istilah “arti” disinonimkan dengan “makna”.
5. Persepsi ibu tentang pengalamannya mengadopsi anak.
• Persepsiibutentangpengalamannyamengadopsianak:(Sebuah)interpretative phenomenological analysis.
• Interpretativephenomenologicalanalysis tentang persepsi ibu mengenai pengalamannya mengadopsi anak.
• Analisisfenomenologisinterpretatiftentangpersepsiibumengenaipengalamannya mengadopsi anak.
• Bagaimanapersepsiibutentangpengalamannyamengadopsianak?(Sebuah)interpretative phenomenological analysis.
• Bagaimanapersepsiibutentangpengalamannyamengadopsianak?(Sebuah) analisis fenomenologis Interpretatif.
Komentar: Formulasi judul ini berasal dari pandangan bahwa mengalami sesuatu berarti mempersepsi sesuatu. Mempersepsi sesuatu berarti memberi makna/arti pada sesuatu. Orang yang mengalami demonstrasi besar, pasti punya persepsi tentang demonstrasi besar itu. Orang yang punya persepsi tentang demonstrasi pasti memberi makna untuk demonstrasi itu. Begitu juga dengan ibu yang punya pengalaman tentang adopsi anak pasti punya makna untuk pengalamannya mengadopsi anak.
BAB III Interpretative Phenomenological Analysis (IPA):Pengantar Singkat dan Formulasi Judul 55
6. Dampak/pengaruh psikologis dari mengadopsi anak bagi ibu.
• Dampak/pengaruhpsikologisdarimengadopsianakbagiibu:(Sebuah)interpretative phenomenological analysis.
• Interpretativephenomenologicalanalysis tentang dampak/pengaruh psikologis dari mengadopsi anak bagi ibu.
• Analisisfenomenologisinterpretatiftentangdampak/pengaruhpsikologisdari mengadopsi anak bagi ibu.
• Bagaimanadampak/pengaruhpsikologismengadopsianakbagiibu?(Sebuah) interpretative phenomenological analysis
• Bagaimanadampak/pengaruhpsikologismengadopsianakbagiibu?Sebuahanalisis fenomenologis interpretatif
Komentar: Formulasi judul ini berasal dari pandangan bahwa pengalaman tertentu dalam hidup partisipan tentu saja secara alami memiliki dampak/pengaruh bagi kondisi psikologisnya. Jadi, istilah “dampak/pengaruh” di sini tidak perlu dikaitkan dengan istilah “dampak/pengaruh” dalam penelitian eksperimental. Dalam penelitian fenomenologis, tidak ada partisipan yang mendapat perlakukan atau intervensi dari peneliti seperti yang dilakukan dalam penelitian eksperimental.
Sebenarnya bunyi judul pertama di setiap nomor adalah bunyi judul yang umum ditemui dalam banyak riset fenomenologis; sementara bunyi judul yang mengikutinya hanyalah variasi dalam merumuskan judul. Tambahan “interpretative phenomenological analysis/analisis fenomenologis interpretatif ” dimaksudkan untuk memperjelas bahwa versi penelitian fenomenologis yang kita gunakan adalah IPA.
Silakan berkreasi dalam merumuskan judul penelitian Anda sejauh Anda berpegang teguh pada upaya memahami pengalaman orang lain yang penuh makna. Bila Anda ingin mengenal macam-macam variasi judul dalam IPA, saya menyarankan membaca artikel dari Joanna M. Brocki dan Alison J. Wearden (2006) berikut ini.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup56
Teks Asli
A critical evaluation of the use of interpretative phenomenological analysis (IPA) in Health Psychology
Abstract
With the burgeoning use of qualitative methods in health research, criteria for judging their value become increasingly necessary. Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) is a distinctive approach to conducting qualitative research being used with increasing frequency in published studies. A systematic literature review was undertaken to identify published papers in the area of health psychology employing IPA. A total of fifty-two articles are reviewed here in terms of the following: methods of data collection, sampling, assessing wider applicability of research and adherence to the theoretical foundations and procedures of IPA. IPA seems applicable and useful in a wide variety of research topics. The lack of attention sometimes afforded to the interpretative facet of the approach is discussed.
Transkreasi
Evaluasi kritis untuk Penggunaan IPA dalam Psikologi Kesehatan
Dengan merebaknya pemakaian penelitian kualitatif di bidang kesehatan, kriteria untuk menilai kelayakan penelitian kualitatif menjadi semakin diperlukan. Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) adalah pendekatan khas dalam menjalankan penelitian kualitatif. Frekuensi penggunaan IPA semakin meningkat dalam penelitian-penelitian yang sudah dipublikasikan. Artikel ini adalah reviu literatur yang sistematis untuk mengindetifikasikan artikel-artikel IPA yang dipublikasikan di bidang psikologi kesehatan. Seluruhnya, ada 52 artikel yang direviu di sini. Reviu yang dilakukan terkait dengan: metode pengumpulan data, sampling, penilaian untuk penerapan IPA yang lebih luas dan juga keterhubungan penelitian dengan dasar-dasar dan prosedur teoretis IPA. IPA tampaknya bisa diterapkan dan bermanfaat dalam beragam topik penelitian. Kami juga membahas kurangnya perhatian pada aspek interpretatif dari IPA.
Artikel itu bisa dijadikan salah satu bacaan yang memantapkan pema-haman Anda tentang formulasi judul dalam IPA. Judul “Critical Evaluation (Evaluasi Kritis)” mungkin memberi kesan berat bagi peneliti pemula dalam IPA. Pemahaman akan seluruh naskah boleh dikesampingkan dahulu.
BAB III Interpretative Phenomenological Analysis (IPA):Pengantar Singkat dan Formulasi Judul 57
Anda cukup mengarahkan perhatian pada tabel yang berisi 52 contoh judul penelitian yang menggunakan IPA.
Untuk sementara, saya cukupkan dahulu pengantar untuk IPA. Saya juga ingin menyarankan Anda untuk memperdalam pemahaman tentang IPA dengan membaca buku Interpretative Phenomenological Analysis yang ditulis oleh Jonathan A. Smith, dkk. Kenapa harus Jonathan A. Smith, dkk.? Karena Jonathan adalah tokoh psikologi yang meletakkan dasar-dasar IPA. Beliau merintis IPA sejak tahun 1990-an dan pada tahun 2009, Jonathan menulis buku Interpretative Phenomenological Analysis itu bersama Michael Larkin dan Paul Flowers. Meskipun dalam buku ini saya memberi porsi yang cukup besar untuk IPA, saya tetap menyarankan Anda menjadikan buku itu sebagai buku rujukan induk. Gambaran singkat tentang buku itu bisa dibaca dalam artikel berikut.
Teks Asli
Making Phenomenological Inquiry Accessible:
A Review of Jonathan A. Smith, Paul Flowers, and Michael Larkin’s
Interpretive Phenomenological Analysis: Theory, Method, and Research
Ronald J. Chenail
Abstract
Jonathan A. Smith, Paul Flowers, and Michael Larkin’s Interpretive Phenomenological Analysis: Theory, Method, and Research is an accessible account of an emergent qualitative psychology methodology which has great potential for studying a variety of psychological areas as well as being applied to studies outside of the behavioral sciences. The authors avoid the complexity
Transkreasi
Membuat Penelitian Fenomenologis Bisa Diakses:
Reviu untuk Buku Jonathan A. Smith, Paul Flowers, dan Michael Larkin yang berjudul Interpretative Phenomenological Analysis: Theory,
Method, and Research
Buku Jonathan A. Smith, Paul Flowers, dan Michael Larkin yang berjudul Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method, and Research (Analisis Fenomenologis Interpretatif: Teori, Metode, dan Penelitian) adalah buku tentang metodologi psikologi kualitatif yang sedang mekar dan mudah diakses untuk dipelajari. Buku ini punya potensi besar untuk digunakan dalam meneliti berbagai bidang psikologis
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup58
found in some texts on phenomenological inquiry and present a simple plan for conducting this style of research.
dan juga bisa diterapkan untuk penelitian-penelitian di luar ilmu-ilmu perilaku. Para penulis buku ( Jonathan, Paul, dan Michael) menghindari kerumitan yang ditemukan dalam beberapa teks tentang penelitian fenomenologis dan memberikan rancangan sederhana untuk menjalankan penelitian fenomenologis dengan IPA.
59
BAB IV
Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Pengantar Singkat dan Formulasi Judul
Kita baru saja menyelesaikan pengantar untuk IPA sebagai salah satu versi penelitian fenomenologis. Sekarang, kita bergeser ke versi penelitian fenomenologis lain, yaitu penelitian fenomenologis deskriptif (PFD). Bila dilihat sejarah kemunculannya, PFD berkembang di awal tahun 1970-an jauh sebelum kemunculan IPA di tahun 1990-an. Jika demikian, mengapa IPA dibicarakan lebih dulu? Dengan sengaja saya memperkenalkan IPA lebih dahulu untuk menghindari penjelasan yang terlalu filosofis di bagian awal. Dalam buku ini, saya memang mengagendakan model pembelajaran yang lebih praktis.
Saya teringat dengan seorang teman kuliah yang berterus terang mengatakan kepada saya, “Apa sih gunanya filsafat? Filsafat yang kita pelajari di S1 dahulu gak kepake.” Di waktu yang terpisah, seorang teman lain juga mengatakan, “Mata kuliah Filsafat itu grambyang (tidak jelas arahnya).” Bila omongan mereka dilekatkan dengan konteks masa kuliah kami dahulu, saya bisa mengerti alasan yang mendasari ketidaktertarikan mereka pada filsafat. Dalam pengamatan saya, materi kuliah filsafat pada waktu itu tidak diperjelas relevansinya bagi psikologi. Filsafat seolah-olah tampil sebagai mata kuliah terpisah yang dimasukkan ke dalam kurikulum psikologi. Belajar dari pengalaman itu, saya berharap materi dalam buku ini bisa memperjelas sedikit demi sedikit relevansi filsafat bagi psikologi, khususnya relevansi filsafat fenomenologis bagi penelitian kualitatif dalam psikologi.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup60
Mari kita kembali ke dua versi penelitian fenomenologis: IPA dan PFD. Saya ingin membicarakan sebentar perbedaan antara dua versi ini sebe lum secara khusus membicarakan PFD. Keduanya adalah penelitian fenomenologis yang berorientasi pada pengalaman. IPA menekankan proses menginterpretasikan pengalaman partisipan dengan menjaga keunikan partisipan dan PFD menekankan proses mendeskripsikan pengalaman parti-si pan untuk menemukan esensi dari pengalaman itu. Itu perbedaan pokok-nya. Mari kita potret lebih dekat lagi.
1. Interpretative Phenomenological Analysis (IPA)
Versi penelitian fenomenologis ini digagas
Gambar 4.1 Jonathan A. Smith. Sumber:http://www.bbk.ac.uk/
psychology/our-staff/jonathan-a-smith
oleh Jonathan A. Smith, seorang profesor psikologi di Universitas Birkbeck, London. IPA menitik beratkan pada proses interpretasi (penafsiran) terhadap pengalaman priba di yang unik. Di bab sebelumnya, kita sudah bertemu dengan tiga pilar yang menopang berdirinya bangunan IPA, yaitu (1) feno me-nologi, (2) hermeneutika, dan (3) idiografi. Pilar ke-3 adalah ciri khas IPA yang paling kental. Dalam psikologi, perspektif yang me-lihat setiap orang sebagai pribadi yang unik dan tidak boleh disamakan de-ngan orang lain disebut perspektif idiografis. IPA dirancang untuk mema hami pengalaman unik dengan meng analisisnya secara mendetail. Meski berfokus pada pengalaman pribadi yang unik, IPA juga mengakui bahwa setiap orang tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosial dan budaya di mana dia hidup. Nah, perhatikan bagaimana kata “personal (pribadi)” yang mun cul dalam tulisan Jonathan A Smith dan Mike Osborn (2007) berikut ini.
Teks Asli
The aim of interpretative phenome nolo-gical analysis (IPA) is to explore in detail how participants are making sense of their personal and social world, and the
Transkreasi
Tujuan dari IPA adalah mengeks-plorasi secara detail bagaimana parti-sipan memaknai dunia pribadi dan sosialnya, dan hal penting dalam
BAB IV Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD):Pengantar Singkat dan Formulasi Judul 61
main currency for an IPA study is the meanings particular experiences, events, states hold for participants. The approach is phenomenological (see Chapter 3) in that it involves detailed examination of the participant’s lifeworld; it attempts to explore personal experience and is con-cerned with an individual’s personal percep tion or account of an object or event, as opposed to an attempt to produce an objective statement of the object or event itself.
penelitian IPA adalah partisipan memberi makna untuk pengalaman tertentu, peristiwa tertentu, atau keadaan tertentu. Pendekatan IPA adalah pendekatan fenomenologis karena repot dengan memeriksa secara mendetail dunia pengalaman partisipan; IPA berupaya mengeksplorasi pengalaman pribadi dan repot dengan persepsi atau cerita pribadi seseorang tentang peristiwa tertentu.
2. Penelitian fenomenologis deskriptif (PFD)
Versi penelitian fenomenologis, ini menekankan pada proses men-deskripsikan pengalaman sampai pada esensi (intisari) dari pengalaman itu sendiri. Tokoh psikologi yang merintis PFD adalah Amedeo Giorgi. Awalnya, dia adalah ilmuwan psikologi yang
Gambar 4.2 Amedeo Giorgi. Sumber: http://
phenomenologyblog.com/?p=485
berminat dengan psikologi eksperimental. Giorgi mendapatkan gelar doktornya di bidang psiko logi eksperimental, tetapi dia kemudian ter tarik dengan fenomenologi dan menjadi editor sampai masa pensiunnya di Journal of Phenome nological Psychology ( Jurnal Psikologi Feno menologis) yang berdiri sejak tahun 1970. PFD yang dikembangkan Giorgi bertujuan untuk menemukan esensi/intisari dari penga-laman partisipan. Tujuan ini sejalan dengan cita-cita Edmund Husserl, pendiri fenomenologi, yang ingin mendeskripsikan pengalaman secara murni, secara asli, apa adanya. Seperti apa pengalaman orisinal itu? Bayangkan, mobil yang Anda tumpangi melaju saat Anda melihat pemandangan dari dalam mobil dengan kaca yang buram karena mengembun. Dalam keadaan seperti itu, Anda akan kesulitan mendeskripsikan pemandangan yang terpampang di depan Anda. Hanya sesudah menghentikan mobil Anda dan melihat langsung tanpa
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup62
diantarai kaca yang mengembun, Anda bisa menggambarkan pemandangan yang Anda lihat. Jadi untuk bisa melihat dengan jelas, peneliti perlu membersihkan diri dari macam-macam teori, penilaian, asumsi, anggapan, atau spekulasi yang sudah bercokol dalam diri sendiri. Kenapa? Semua itu potensial merusak keaslian pengalaman partisipan. Dalam fenomenologi, pembersihan diri itu disebut epochē (bracketing/meletakkan dalam kurung). Kita sudah sering ketemu dengan istilah epochē ini dan masih akan sering menemuinya karena epochē adalah konsep sentral dalam PFD. Mari kita simak dahulu penjelasan Darren Langdridge (2007:105) tentang apa itu PFD.
Teks Asli
Descriptive phenomenological psychology is the name for one of the earliest applications of phenomenological philosophy to psychology. This approach remains faithful to Husserl ’s philosophy and as such involves a search for essences following epoché and a phenomenological reduction.
Transkreasi
Psikologi fenomenologis deskriptif (dalam buku ini kita menyebutnya PFD) adalah nama untuk salah satu penerapan filsafat fenomenologis ke dalam psikologi. Pendekatan ini tetap setia pada pemikiran filosofis Edmund Husserl dan berupaya menemukan esensi (inti) dari pengalaman dengan menjalankan epochē dan reduksi fenomenologis.
Saat menganalisis data, peneliti dituntut untuk menjalankan epochē agar bisa menangkap inti dari pengalaman partisipan dan mendeskripsikannya. Itulah cita-cita PFD. Oleh karena itu, peneliti yang merasa sulit untuk melepaskan diri dari kendali teori/pemikiran/asumsi/pandangan/perspektif dalam dirinya dan punya kecenderungan mencocok-cocokkan pengalaman partisipan dengan teori sebaiknya tidak menggunakan fenomenologi deskriptif ini.
Nah, mudah-mudahan Anda sudah bisa sedikit menangkap tentang perbedaan antara IPA dan PFD. Mungkin muncul pertanyaan: Jika epochē adalah ciri yang kental dari PFD, bagaimana dengan IPA? Apakah IPA tidak menganggap penting epochē itu? Tentu saja, IPA yang mendapat makanan dari fenomenologi juga menjalankannya epochē itu. Hanya saja, ada perbedaan dalam cara IPA dan PFD menjalankan epochē. Dalam IPA, epochē
BAB IV Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD):Pengantar Singkat dan Formulasi Judul 63
adalah proses alami yang terjadi bila kita memusatkan perhatian sepenuhnya pada pengalaman partisipan. Dengan epochē, kita membuka diri untuk merevisi pandangan-pandangan pribadi kita sampai pandangan partisipan menjadi jelas. Epochē sudah mulai dijalankan pada saat wawancara untuk mengumpulkan data, dan berlanjut dalam analisis data, dan interpretasi data. Perhatikan apa yang ditulis Jonathan A. Smith, Paul Flowers, dan Michael Larkin (2009:64) tentang epochē berikut ini.
Teks Asli
During the interview phase of the research project, you are leaving your research world …. Here the participant has experiential expertise and is the sole focus for your attention. By focusing on attending closely to your participant’s words, you are more likely to park or bracket your own pre-existing concerns, hunches, and theoretical hobby horses. It is not that you should not be curious and questioning; it is that your questioning at this phase of the project should all be generated by attentive listening to what your participant has to say.
Transkreasi
Selama tahap wawancara dalam penelitian Anda, Anda meninggalkan dunia penelitian Anda (teori, keinginan, dan harapan Anda dalam penelitian)…. Di sini partisipan adalah pakar yang bercerita menurut pengalamannya dan menjadi satu-satunya pusat perhatian Anda. Dengan sungguh-sungguh memusatkan perhatian pada kata-kata partisipan (selama wawancara), besar kemungkinan Anda menghentikan sebentar atau mengurung (meng-epochē) hal-hal yang menjadi kesukaan Anda, firasat-firasat Anda, dan pandangan-pandangan teoretis yang menjadi favorit Anda. Epochē tidak berarti bahwa Anda tidak lagi ingin tahu atau tidak lagi bertanya; epochē berarti semua pertanyaan Anda pada saat wawancara muncul karena Anda mendengarkan sungguh-sungguh apa yang partisipan Anda katakan.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup64
A. Epochē sebagai Pilar PFD
Saya ulangi dan tekankan lagi bahwa sikap dasar yang mutlak dimiliki oleh peneliti yang ingin menjalankan PFD adalah epochē. Epochē ini akan mendasari dan mengiringi seluruh proses analisis data. Dengan menggunakan istilah “deskriptif ”, PFD ingin menekankan proses deskripsi saat ber-epochē. Jika Anda di suatu sore duduk dengan tenang di tepi pantai dan lepas dari macam-macam pikiran dan perasaan yang berseliweran, maka Anda punya peluang untuk mendeskripsikan sunset itu dengan baik. Epochē berarti saat membaca transkrip partisipan, peneliti dalam keadaan tenang dan tidak terusik oleh teori/pemikiran/asumsi/pandangan/prasangka/praduga tertentu.
Dengan menjalankan epochē saat membaca transkrip, peneliti bisa masuk ke dalam dunia pengalaman partisipan. Dalam dunia pengalaman itu, ada macam-macam fenomena (peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian mental). Peneliti kemudian mendeskripsikan fenomena-fenomena itu.
Dalam keadaan epochē, kita menenangkan diri dari gejolak pikiran dan perasaan kita sendiri. Dalam keadaan tenang, pikiran menjadi terfokus. Dalam keadaan yang terfokus itu, fenomena-fenomena akan berbicara sendiri. Bila kita mengambil sunset sebagai fenomena, sunset akan menampilkan sendiri keindahannya bagi orang yang melihatnya dengan tenang dan terfokus. Sebaliknya, bila pikiran kita terpencar dan kisruh, sunset tidak akan menampakkan keindahannya. Begitulah, epochē membuat peneliti bisa terhubung dengan fenomena-fenomena dalam pengalaman partisipan. Epochē adalah sikap dasar peneliti untuk bisa menjalankan reduksi fenomenologis, yaitu proses secara bertahap menembus pengalaman partisipan sampai pada esensi (inti) dari pengalaman itu.
Kita sudah ketemu dengan tiga poin penting dalam PFD, yaitu (1) peneliti menjalankan epochē dan reduksi fenomenologis, (2) dalam keadaan epochē itu, peneliti membuat mendeskripsikan pengalaman partisipan, dan (3) peneliti menemukan esensi (inti) dari pengalaman partisipan. Ketiga poin itu adalah inti dari PFD yang digagas oleh Amedeo Giorgi, seperti yang ditulis oleh Linda Finlay (2009:7) berikut ini.
BAB IV Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD):Pengantar Singkat dan Formulasi Judul 65
Teks Asli
Giorgi (1997), more straightforwardly, argues that the phenomenological method encompasses three interlocking steps: (1) phenomenological reduction, (2) description, and (3) search for essences.
Transkreasi
Giorgi secara lebih gamblang berpen-dapat bahwa metode fenomenologis meliputi tiga langkah yang saling ter-kait, yaitu (1) menjalankan reduksi feno menologis, (2) membuat deskripsi (tentang pengalaman partisipan), dan (3) mencari esensi-esensi dari pengalaman partisipan.
Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan, apakah PFD itu? Ketiga langkah itu harus dibicarakan. Saya berharap wajah PFD sebagai penelitain kualitatif yang berkembang dalam psikologi sudah Lebih jelas. Kita akan kembali membicarakan PFD ini secara lebih dalam lagi di Bab IX, Bab X, dan Bab XI.
B. Double Descriptive (Deskripsi Ganda)
Dalam Bab III saat kita membicarakan IPA, kita bertemu dengan istilah double-hermeneutic (penafsiran ganda) yang menandai hubungan antara partisipan dan peneliti fenomenologis. Kita segarkan lagi apa makna dari double hermeneutic itu. Partisipan adalah penafsir untuk pengalaman hidupnya. Selanjutnya, peneliti IPA datang dan menjadi penafsir untuk penafsiran partisipan. Singkatnya, double-hermeneutic berarti peneliti menaf-sirkan penafsiran partisipannya.
Aktivitas ganda seperti itu sebenarnya tidak eksklusif terjadi dalam IPA. Dalam PFD, kita juga menemukan aktivitas ganda seperti itu. Aktivitas ganda itu bisa kita sebut sebagai double descriptive (deskripsi ganda). Prosesnya begini.
Partisipan mendeskripsikan pengalaman pribadinya secara natural dalam bahasa percakapan sehari-hari dan peneliti mendeksripsikan pengalaman partisipan secara fenomenologis. Singkatnya, peneliti mendeskripsikan secara fenomenologis deskripsi natural dari partisipannya.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup66
Perhatikan bahwa deskripsi pertama bersifat natural dan deskripsi kedua bersifat fenomenologis. Apa artinya deskripsi natural dan deskripsi fenomenologis? Istilah “natural” dan “fenomenologis” di sini tidak bisa dile-paskan dari pemikiran Edmund Husserl yang merupakan rujukan utama dari PFD. Husserl membagi sikap menjadi dua, yaitu (1) sikap natural (natural attitude) dan (2) sikap fenomenologis (phenomenological attitude). Sikap natural adalah sikap umum yang ditemui pada banyak orang di mana mereka belum menjalankan epochē (masih dipengaruhi prasangka, praduga, pra penilaian, spekulasi, asumsi); sementara sikap fenomenologis adalah sikap ilmiah yang ditemui pada orang yang menjalankan epochē (membersihkan diri dari pengaruh prasangka, praduga, prapenilaian, spekulasi, asumsi). Orang yang hidup dalam sikap natural akan menjalankan deskripsi natural; sementara orang yang hidup dalam sikap fenomenologis akan menjalankan deskripsi fenomenologis.
Saat mewawancarai partisipan, peneliti PFD akan mendengarkan laporan atau kisah tentang pengalaman hidup partisipannya. Partisipan mendeskripsikan pengalamannya dengan sikap natural. Hasil dari cerita itu adalah transkrip dan transkrip itu adalah deskripsi natural. Peneliti kemudian ingin memahami deskripsi natural (transkrip) itu dengan masuk ke dalam transkrip dengan menjalankan epochē. Buah atau hasil dari masuk ke transkrip plus epochē adalah deskripsi fenomenologis. Inilah proses inti yang terjadi dalam analisis data PFD yang bisa kita skemakan sebagai berikut.
Pengalaman hidup PARTISIPAN TRANSKRIP PENELITI Epochē
C. Formulasi Judul dalam PFD
Penelitian fenomenologis adalah penelitian yang secara eksplisit menekankan pentingnya kajian tentang pengalaman langsung (lived experience). PFD adalah penelitian fenomenologis yang berkembang pertama kali dalam psikologi, sekitar dua dekade sebelum kemunculan IPA. Jika kita melakukan penelusuran internet, penelitian fenomenologis
BAB IV Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD):Pengantar Singkat dan Formulasi Judul 67
yang menggunakan IPA lebih mudah dideteksi karena pada judul biasanya jelas tertulis “interpretative phenomenological analysis”. Memang sebelum IPA muncul, penelitian fenomenologis yang dikembangkan Giorgi dan rekan-rekannya umumnya dikenal dengan nama “psikologi fenomenologis”. Istilah deskriptif muncul kemudian untuk menunjukkan secara lebih tegas perbedaan antara penelitian fenomenologis versi Giorgi (dan kawan-kawan) dan penelitian fenomenologis versi Jonathan A. Smith (dan kawan-kawan).
Formulasi atau perumusan judul-judul PFD cukup bervariasi. Berikut ini adalah kata-kata kunci yang bisa Anda gunakan untuk menelusuri jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi yang berbahasa Inggris di mesin pencari Google.
• Thelivedexperienceof (pengalaman tentang ....) • Understanding the lived experience of (memahami pengalaman tentang
....)• Exploring the lived experience of ... (mengeksplorasi pengalaman
tentang ....)• A phenomenological research into the lived experience of (Penelitian
fenomenologis untuk pengalaman tentang ....) • A phenomenological research of the lived experience of (Penelitian
fenomenologis tentang pengalaman mengenai ....)
Saat mengetik kata-kata kunci di atas pada halaman Google, Anda akan disodori begitu banyak hasil penelitian fenomenologis yang menggunakan PFD. Informasi dalam Kotak 4.1 adalah contoh hasil penelusuran pada tanggal 16 Mei 2017.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup68
Kot
ak 4
.1 P
enel
usur
an O
nlin
e Jud
ul P
FD
Sum
ber:
ww
w.go
ogle.
com
BAB IV Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD):Pengantar Singkat dan Formulasi Judul 69
Masih ada beberapa variasi lain dalam merumuskan atau menformulasi-kan judul. Anda bebas untuk membunyikan secara kreatif judul penelitian yang Anda anggap bisa menarik perhatian pembaca. Berikut ini, saya akan memberi contoh tentang beberapa bunyi PFD yang bisa digunakan dalam bahasa Indonesia. Kita, misalnya, tertarik dengan fenomena “sembuh dari kecanduan alkohol”. Ketertarikan kita itu bisa diformulasikan menjadi judul dalam beragam cara, seperti yang ditampilkan dalam Kotak 4.2.
Kotak 4.2 Contoh-contoh Formulasi Judul dalam PFD
1. Penelitian fenomenologis (deskriptif ) tentang pengalaman sembuh dari kecanduan pada alkohol.Pengalaman sembuh dari kecanduan pada alkohol: (sebuah) penelitian
fenomenologis (deskriptif ).Persepsi tentang sembuh dari kecanduan pada alkohol: (sebuah) penelitian
fenomenologis (deskriptif ).
2. Investigasi fenomenologis (deskriptif ) tentang pengalaman sembuh dari kecanduan pada alkohol. Pengalaman sembuh dari kecanduan pada alkohol: (sebuah) investigasi
fenomenologis (deskriptif ).Persepsi tentang sembuh dari kecanduan pada alkohol: (sebuah) investigasi
fenomenologis (deskriptif ).
3. Eksplorasi fenomenologis (deskriptif ) tentang pengalaman sembuh dari kecanduan alkohol.Pengalaman sembuh dari kecanduan alkohol: (sebuah) eksplorasi
fenomenologis (deskriptif ).Persepsi tentang sembuh dari kecanduan alkohol: (sebuah) eksplorasi
fenomenologis (deskriptif ).
4. Studi fenomenologis (deskriptif ) tentang pengalaman sembuh dari kecanduan alkohol.Pengalaman sembuh dari kecanduan alkohol: (sebuah) studi fenomenologis
(deskriptif ).Persepsi tentang sembuh dari kecanduan alkohol: (sebuah) studi
fenomenologis (deskriptif ).
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup70
5. Kajian fenomenologis (deskriptif ) tentang pengalaman sembuh dari kecanduan alkohol.Pengalaman sembuh dari kecanduan alkohol: (sebuah) kajian fenomenologis
(deskriptif ).Persepsi tentang sembuh dari kecanduan alkohol: (sebuah) kajian
fenomenologis (deskriptif ).
Komentar: Kata “deskriptif ” sengaja saya tempatkan dalam kurung untuk menunjukkan bahwa peneliti bisa menggunakannya atau tidak menggunakannya. Perhatikan juga bahwa kata “pengalaman” boleh diganti dengan “persepsi”. Dalam fenomenologi, mengalami berarti mempersepsi. Orang yang mengalami sesuatu pasti mempersepsi sesuatu itu. Judul-judul yang dicetak miring adalah variasi judul yang bisa Anda gunakan.
1. Memahami pengalaman sembuh dari kecanduan alkohol: (sebuah) penelitian/investigasi/eksplorasi/studi/kajian fenomenologis.
2. Mengeksplorasi pengalaman sembuh dari kecanduan alkohol: (sebuah) penelitian/investigasi/eksplorasi/studi/kajian fenomenologis.
3. Mengkaji pengalaman sembuh dari kecanduan alkohol: (sebuah) penelitian/investigasi/eksplorasi/studi/kajian fenomenologis.
4. Meneliti pengalaman sembuh dari kecanduan alkohol: (sebuah) penelitian/investigasi/eksplorasi/studi/kajian fenomenologis
Komentar: Formulasi judul di atas menggunakan kata kerja yang ditempatkan di bagian awal. Istilah “memahami” sejalan dengan aktivitas pokok dalam penelitian fenomenologis di mana peneliti mendengarkan pengalaman partisipan. Buah dari sikap “mendengarkan” itu adalah pemahaman.
1. Studi tentang pengalaman sembuh dari kecanduan pada alkohol
2. Studi tentang dunia kehidupan pecandu alkohol
Komentar: Anda juga bisa menghilangkan kata fenomenologis pada judul dan cukup menggunakan kata “pengalaman (lived experience)” atau “dunia kehidupan (life-world)” partisipan yang akan diteliti. Kata “fenomenologis” bisa dihilangkan karena fenomenologi itu sendiri pada dasarnya adalah penelitian tentang pengalaman hidup atau dunia kehidupan subjektif seseorang.
BAB IV Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD):Pengantar Singkat dan Formulasi Judul 71
1. Apa artinya sembuh dari kecanduan alkohol? (Sebuah) penelitian/investigasi/eksplorasi/studi/kajian fenomenologis
2. Penelitian/investigasi/eksplorasi/studi/kajian fenomenologis tentang bagaimana remaja/wanita sembuh dari kecanduan alkohol
3. Bagaimana remaja/wanita sembuh dari kecanduan alkohol? (Sebuah) penelitian/investigasi/eksplorasi/studi/kajian fenomenologis
4. Penelitian/investigasi/eksplorasi/studi/kajian fenomenologis tentang bagaimana remaja/wanita sembuh dari kecanduan alkoholKomentar: Anda juga bisa menggunakan kata tanya untuk menonjolkan pertanyaan penelitian Anda pada judul. Kata tanya yang umum digunakan adalah “bagaimana’ dan “apa”. Dalam judul yang menggunakan kata tanya “bagaimana”, subjek/partisipan penelitian biasanya menjadi jelas.
The private theater: a phenomenological investigation of daydreaming.
Teater/bioskop pribadi: Investigasi fenomenologis tentang (pengalaman) mengkhayal.
Komentar: Judul yang terakhir ini adalah judul penelitian J. Morley (1998). Saya menampilkannya di sini untuk memberi contoh bahwa peneliti fenomenologis deskriptif bisa membuat judulnya tampil menarik dengan menampilkan metafora atau bahasa kias atau ibarat yang menggambarkan pengalaman partisipan. Judul seperti ini memang menarik. Biasanya judul itu datang sebagai insight yang membuat peneliti merasakan “benang merah” yang menghubungkan pengalaman seluruh partisipan dalam penelitiannya. Berdasarkan contoh tersebut, benang merah yang menghubungkan semua partisipan adalah bahwa mereka menikmati khayalan pribadinya ibarat orang yang menikmati tontonan di teater atau bioskop.
73
BAB V
Persiapan ke Lapangan: Literatur dan Pengumpulan Data
Pemahaman dasar tentang dua versi penelitian fenomenologis sudah kita lewati. Kita sekarang akan membicarakan upaya-upaya apa saja yang perlu dipersiapkan oleh peneliti sebelum turun ke lapangan untuk menemui partisipan-partisipannya. Peneliti fenomenologis harus siap menjalankan prinsip-prinsip fenomenologis. Untuk memeriksa ke-fenomenologis-an diri sendiri, pertanyaan-pertanyaan pokok berikut seharusnya bisa dijawab.
1. Apa itu penelitian fenomenologis? Penelitian reflektif tentang pengalaman subjektif partisipan.
2. Apa artinya “fenomena” dalam penelitian fenomenologis? Peristiwa/kejadian/aktivitas mental apa saja yang muncul dalam
kesadaran partisipan.
3. Siapakah partisipan/subjek penelitian fenomenologis? Orang yang mengalami secara subjektif dan secara langsung fenomena
yang menjadi judul penelitian.
4. Bagaimana membuat judul penelitian fenomenologis? Caranya bervariasi. Yang penting peneliti membuat judul yang ber-
pegang pada upaya memahami pengalaman orang lain dari perspektif orang pertama (si aku yang mengalami suatu peristiwa).
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup74
5. Apa yang diperlukan dari peneliti agar fenomena-fenomena dalam kesadaran partisipan bisa dideskripsikan/diinterpretasikan dengan baik?
Epochē/Einklämmerung/bracketing/mengurung pengetahuan yang sudah bercokol dalam diri sendiri.
6. Apa perbedaan antara IPA dan PFD? IPA menekankan proses interpretatif dalam memahami pengalaman
personal yang unik; sementara PFD menekankan epochē dalam men-deskripsikan pengalaman yang umum ditemui semua partisipan.
7. Kualitas penting apa saja yang dibutuhkan dari seorang peneliti fenomenologis?
Mengakui relativitas persepsi (perbedaan persepsi antarpribadi), bisa men jalankan epochē, memiliki kemampuan mendengarkan, dan bisa berempati.
Bagaimana kita tahu apakah peneliti sudah siap menjalankan penelitian fenomenologis? Sederhana saja, calon-calon peneliti fenomenologis sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyan tersebut. Karena pertanyaan-pertanyaan itu sudah dilengkapi dengan jawaban, calon-calon peneliti diharapkan memahami dan bisa mempraktikkan jawaban-jawaban itu dalam aktivitas risetnya. Pernyataan-pernyataan dalam Kotak 5.1 bisa Anda gunakan untuk memeriksa kesiapan-diri.
Kotak 5.1 Pemeriksaan Pemahaman Fenomenologis sebelum Pengumpulan Data
No. Pernyataan Cek
1. Sebagai peneliti, saya tahu alasan saya memilih penelitian fenomenologis, bukan studi kasus, penelitian grounded theory, penelitian etnografis, atau penelitian lain dalam tradisi kualitatif.
√
2. Sebagai peneliti, saya tahu “fenomena” apa yang sudah menarik perhatian saya dan untuk selanjutnya saya serius meneliti fenomena itu.
√
3. Sebagai peneliti, saya tahu apa itu epochē dan punya komitmen untuk menjalankannya dalam penelitian.
√
BAB V Persiapan ke Lapangan:Literatur dan Pengumpulan Data 75
4. Sebagai peneliti, saya bisa merumuskan judul penelitian fenomenologis saya sesuai dengan versi penelitian fenomenologis yang saya pilih (baik IPA maupun PFD).
√
5. Sebagai peneliti, saya tahu bahwa saya harus mengakses pengalaman partisipan dan memastikan bahwa semua partisipan saya homogen.
√
6. Sebagai peneliti, saya tahu alasan kenapa saya memilih IPA dan bukan PFD atau sebaliknya memilih PFD dan bukan IPA.
√
7. Sebagai peneliti, saya tahu bahwa saya akan mengembangkan empat kualitas peneliti fenomenologis: (1) menerima relativitas persepsi, (2) menjalankan epochē, (3) menjadi pendengar yang baik, dan (4) bisa berempati.
√
Saya anggap Anda tidak lagi bermasalah dengan tujuh poin di atas. Artinya, secara konseptual Anda sudah cukup siap. Bagaimanapun, siap secara konseptual belum cukup. Anda juga perlu siap untuk menerapkan konsep-konsep yang Anda miliki di lapangan. Partisipan yang akan kita temui punya pengalaman dan kita ingin mengakses pengalaman subjektif itu lewat jalur komunikasi yang disebut wawancara. Peneliti perlu melakukan persiapan yang baik agar wawancaranya berjalan baik. Wawancara yang berjalan baik akan menghasilkan data yang layak untuk dianalisis.
A. Bacaan Literatur dan Sikap Peneliti
Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, memiliki judul adalah langkah paling awal dan menjalankan riset. Saat membuat judul penelitian, peneliti fenomenologis perlu memperhatikan manfaat dari “pengalaman” yang diteliti bagi disiplin/ilmu yang digeluti. Jika peneliti berasal dari fakultas psikologi, maka diharapkan bisa memberi manfaat bagi psikologi. Begitu juga dengan peneliti-peneliti dari disiplin ilmu kemanusiaan lain, seperti keperawatan, komunikasi, kepustakaan, atau kesehatan masyarakat.
Segera sesudah memiliki judul, peneliti perlu segera melakukan survei pendahuluan untuk memprediksi apakah proses pengumpulan data nantinya tidak akan mengalami kesulitan. Artinya, peneliti perlu yakin bahwa dia bisa menemukan orang-orang yang mau dan terbuka untuk diwawancarai.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup76
Apa gunanya memiliki judul yang bagus kalau calon-partisipan yang akan diwawancarai tidak bersedia? Sejak awal, peneliti diharapkan sudah mulai menjalin kontak atau komunikasi dengan calon partisipan. Kalau calon-partisipan sudah bersikap menerima, maka kita bisa lebih tenang.
Sambil menunggu waktu yang tepat untuk menemui langsung partisi-pan, peneliti bisa memusatkan perhatiannya pada penulisan latar belakang/pendahuluan penelitian (umumnya Bab I), reviu literatur/tinjauan pustaka (umumnya Bab II), dan metode penelitian (umumnya Bab III). Jadi, ada dua persiapan: (1) persiapan yang terkait dengan bacaan literatur yang akan mengisi segmen latar belakang dan reviu literatur dan (2) persiapan meto-dologis yang akan mengisi segmen metode penelitian. Mari kita lihat lebih dekat.
1. Persiapan yang Terkait dengan Bacaan Literatur
Persiapan ini terkait dengan penelusuran literatur dan menuliskan hasil penelusuran itu. Bacaan literatur itu biasanya dibutuhkan untuk latar belakang penelitian dan reviu literatur. Carilah literatur-literatur yang dirasakan terkait dengan pengalaman yang ingin diteliti. Kalau ingin meneliti tentang pengalaman menjadi single mother, carilah literatur yang terkait dengan itu, seperti parenting (peran sebagai orangtua), konstelasi (susunan) keluarga, penelitian cross-cultural tentang keluarga, peran ibu, relasi ibu-anak, dan lain-lain. Literatur yang dicari tidak harus berbicara persis seperti bunyi judul penelitian. Silakan bebas mencari literatur sejauh literatur itu “bersinggungan” dengan judul penelitian dan memperjelas kepada pembaca fenomena yang ingin kita teliti. Sebagai contoh, kita ingin meneliti pengalaman penderita hepatitis. Sebelum bertemu partisipan untuk wawancara, kita menulis sebagai berikut.
Penelitian ini berfokus pada pengalaman penderita Hepatitis A. Hepatitis A adalah infeksi akut akibat virus yang berdampak pada pembengkakan hati. Virus itu ditemukan dalam tinja sehingga sering kali menular lewat makanan yang tidak higienis atau kontak pribadi yang intim, seperti hubungan seksual. Penyakit hepatitis A adalah penyakit yang akut dan berlangsung antara dua minggu sampai dua bulan. Tidak ada perawatan medis untuk penyakit ini.
BAB V Persiapan ke Lapangan:Literatur dan Pengumpulan Data 77
Pasien diminta untuk istirahat, berhenti mengonsumsi alkohol, dan makan makanan sehat.
Perhatikan bagian yang dicetak miring. Dari mana peneliti men-dapatkan informasi itu? Tentu saja dari literatur. Dengan membaca literatur, kita memiliki gambaran tentang asumsi-asumsi, teori-teori, dan perspektif-perspektif yang punya kaitan dengan judul atau fenomena yang ingin kita teliti. Mungkin muncul pertanyaan: bukankah sebelumnya dikatakan bahwa peneliti fenomenologis perlu menjalankan epochē atau mengurung teori? Betul. Untuk mengurung teori, harus ada teori yang dikurung. Untuk mengesampingkan teori, harus ada teori yang dikesampingkan. Mengesampingkan teori bukan berarti tidak tahu teori. Mengesampingkan teori berarti tahu teori dan tahu juga potensinya dalam mengotori peneliti dalam melihat pengalaman asli partisipan. Jadi, tidak ada salahnya mengisi diri kita dengan teori atau hasil-hasil riset dalam jurnal ilmiah. Perhatikan apa yang ditulis oleh Dahlberg, Dahlberg, dan Nyström (2008:174) berikut ini.
Teks Asli
It is to the researcher’s advantage to be acquainted ... with published research reports and other types of literature. However ... it can be advisable not to read too much ... existing literature on the very phenomenon. Knowing ... much about “how it is” can make it hard to “briddle” enough to enable the researcher to see something new.
Transkreasi
Ada manfaatnya bagi peneliti bila dia mengenal laporan-laporan penelitian yang dipublikasikan atau jenis-jenis literatur yang lain. Bagaimanapun ... peneliti disarankan untuk tidak membaca terlalu banyak ... literatur yang beredar tentang fenomena yang sedang diteliti. Bila peneliti tahu .... terlalu banyak tentang “bagaimana pengalaman partisipan”, peneliti akan kesulitan melihat sesuatu yang baru (dalam pengalaman partisipannya).
Agar tidak mengalami kesulitan dalam melakukan epochē, kita disarankan tidak membaca terlalu banyak. Tampaknya Dahlberg, dkk. (2008) ingin mengatakan bahwa semakin banyak teori yang Anda baca,
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup78
semakin besar peluang Anda dicengkeram teori itu. Saya kira, pendapat itu tidak sepenuhnya benar. Fenomenologi bukan soal menghindari banyak literatur untuk dibaca, tetapi bagaimana peneliti secara pribadi menyikapi berbagai literatur yang dibaca. Persoalannya bukan bacaan, tetapi sikap terhadap bacaan. Membaca literatur itu perlu, tetapi ada saatnya, teori atau hasil riset itu perlu disuspensi. Nah, kita sekarang mendapat lagi istilah baru, yaitu suspensi. Suspensi adalah istilah lain yang juga sering digunakan oleh peneliti fenomenologis untuk epochē/bracketing/netralisasi diri/mengurung teori dan penilaian. Suspensi di sini tidak ada hubungannya dengan gerakan fleksibel roda mobil saat melaju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), suspensi diberi arti berikut ini.
suspensi/sus·pen·si/ /suspénsi/ n 1 pelaksanaan penundaan atau penangguhan sesuatu untuk sementara; 2 pemecatan (dari jabatan, pekerjaan) untuk sementara waktu; 3 Kim sistem koloid zat padat yang terserak dalam zat cair, partikelnya tidak mudah mengendap karena kecil ukurannya dan tidak mudah menggumpal karena sering menolak; 4 Tek sistem penggantungan roda mobil.
Suspensi dalam penelitian fenomenologis adalah suspensi dalam makna yang kedua tersebut. Itulah epochē. Kita tidak menghilangkan asumsi/teori/anggapan/penilaian. Tidak mungkin dihilangkan karena kita sudah mengingatnya dan menjadi bagian dari diri kita. Kita hanya perlu menyingkirkannya atau “memecatnya” untuk sementara agar tidak mengganggu kita dalam melihat pengalaman orang lain dengan jernih. Kita perjelas lagi.
epochē = Einklämmerung = bracketing = suspension = upaya meletakkan dalam kurung
BAB V Persiapan ke Lapangan:Literatur dan Pengumpulan Data 79
2. Persiapan Diri Pra-wawancara
Persiapan ini adalah bagian yang paling menentukan dalam wawan-cara fenomenologis. Persiapan mental yang paling utama adalah suspensi atau epochē. Pembimbing penelitian akan mengecek apa saja yang sudah peneliti lakukan untuk menjalankan suspensi atau epochē itu. Bagaimana pembimbing mengetahui suspensi atau epochē yang dijalankan peneliti? Suspensi/epochē itu bisa diketahui dari cara peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan dalam panduan wawancara. Dalam lingkungan penelitian fenomenologis di Amerika, panduan wawancara itu disebut interview guide; sedangkan dalam lingkungan Inggris, disebut interview schedule. Dari pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam panduan wawancara, kita bisa merasakan pertanyaan yang mencerminkan epochē (pertanyaan netral) dan yang tidak mencerminkan epochē (pertanyaan yang menggiring pada jawaban tertentu).
B. Wawancara Semi-terstruktur dan Panduan Wawancara
Pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian fenome-nologis adalah wawancara dan bentuk wawancara yang umum digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Ciri dari wawancara semi-terstruktur adalah penggunaan panduan wawancara (interview guide/interview proto-col). Panduan wawancara ini memainkan peran penting dalam menarik informasi keluar dari pengalaman partisipan. Tanpa panduan wawancara, peneliti pemula akan mengumpulkan data yang kurang mendalam sehingga berdampak pada kesulitan menganalisis data. Panduan wawancara yang buruk akan menghasilkan data yang kurang atau tidak layak untuk diteliti.
Untuk itu, panduan wawancara perlu didiskusikan baik dengan pem-bimbing skripsi/tesis/disertasi maupun dengan teman sejawat. Dalam penelitian fenomenologis, panduan wawancara diharapkan berisi pertanyaan-pertanyaan netral atau pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan epochē. Sangat disayangkan bila peneliti sudah mewawancarai partisipan dan hasilnya tidak layak dianalisis karena pertanyaan-pertanyaan yang kotor dengan asumsi atau prasangka sehingga jawaban partisipan juga tidak menggambarkan pengalaman orisinalnya. Untuk itu, perlu kita berlatih mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang netral dalam panduan wawancara.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup80
C. Panduan Wawancara dalam IPA
Untuk sekadar menyegarkan ingatan, metode wawancara individual umumnya dibagi menjadi tiga: (1) wawancara terstruktur, (2) wawancara semi-terstruktur, dan (3) wawancara tidak terstruktur. Penelitian fenomenologis menganjurkan wawancara semi-terstruktur. Dalam wawan-cara semi-testruktur, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan pokok yang bisa dikembangkan lebih jauh atau diperdalam lagi saat mendengarkan jawaban partisipan. Apakah peneliti boleh mengalir saat wawancara tanpa harus menggunakan panduan? Tentu saja boleh, tetapi untuk bisa mengalir seperti itu, Anda butuh “jam terbang” yang tinggi. Tidak perlu tergesa-gesa. Ada saatnya ketika Anda sudah terampil bertanya, Anda tidak lagi direpotkan dengan penyusunan pertanyaan-pertanyaan sebelum ke lapangan.
Saya menganggap Anda masih butuh panduan wawancara. Sebelum menyusun panduan wawancara, peneliti perlu menyadari pentingnya epochē dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Agar informasi atau data yang didapatkan dari partisipan bisa dianalisis secara fenomenologis, peneliti perlu belajar mengenali jenis-jenis pertanyaan yang fenomenologis dan yang bukan fenomenologis. Tentang jenis-jenis pertanyaan dalam penelitian fenomenologis dengan IPA, saya mengikuti pembagian Jonathan A. Smith dkk (2009:59-62) (lihat Kotak 5.2).
Kotak 5.2 Pertanyaan-pertanyaan untuk Menggali Pengalaman
Jenis Contoh Pertanyaan
Deskriptif Bisa ceritakan (beri gambaran tentang) apa yang Anda kerjakan di sekolah luar biasa (SLB)?
Naratif Bisa ceritakan bagaimana (kisahnya) sampai Anda bisa bekerja di sini?
Struktural Bagaimana tahapan (langkah-langkah dalam) memberi informasi kepada anak autis?
Kontras Apa perbedaan antara mengajar anak normal dan anak berkebutuhan khusus?
Evaluative Apa yang Anda rasakan setelah melewati hari kerja yang menyebalkan?
BAB V Persiapan ke Lapangan:Literatur dan Pengumpulan Data 81
Sirkuler Menurut Anda, apa pendapat atasan atau rekan kerja Anda tentang cara Anda menjalankan tugas?
Komentar: Dalam pertanyaan ini, kita sebenarnya bertanya tentang pengalaman partisipan, tetapi “mengatasnamakan” orang lain. Kita mendapat informasi tentang partisipan dengan cara memutar atau tidak langsung sehingga disebut sirkuler.
Komparatif Menurut Anda, seperti apa hidup Anda seandainya Anda bekerja di tempat lain?
Komentar: Dalam pertanyaan ini, partisipan diminta mengungkapkan perasaannya bila bekerja di tempat lain. Jawaban yang diberikan bisa memberi gambaran tentang tempat kerjanya saat ini: Lebih/kurang nyaman? Lebih/kurang senang? Lebih/kurang …. dan seterusnya.
Jika partisipan memberi jawaban yang dirasa masih kurang, peneliti sebaiknya segera memperdalam. Perhatikan dan ikuti betul jawaban subjek dan bila ada jawaban yang kurang jelas segera minta kejelasan. Ingatlah selalu bahwa misi kita mewawancarai adalah mendapatkan banyak informasi tentang pengalaman partisipan. Informasi yang banyak akan membantu kelancaran dalam analisis data. Berikut ini adalah dua teknik meminta kejelasan saat wawancara sedang berlangsung.
Prompting : Bisa ceritakan lebih jauh tentang itu?
Probing : Apa yang Anda/kamu maksud dengan “merasa dibuang”?
Jadi, kita bisa memperdalam jawaban partisipan dengan menggunakan teknik prompting dan probing. Dalam bahasa Inggris, prompt berarti tin-dakan mendorong pembicara yang ragu untuk berbicara; sementara probe berarti upaya menemukan informasi yang tersembunyi. Prompting dalam penelitian fenomenologis berarti mengajukan prompt, yaitu pertanyaan yang dimaksudkan untuk mendorong partipan bercerita lebih banyak lagi tentang pengalamannya; sementara probing berarti mengajukan probe, yaitu pertanyaan yang dimaksudkan untuk meminta klarifikasi lebih lanjut tentang istilah atau ungkapan tertentu yang belum jelas atau masih samar.
Dalam mengajukan pertanyaan, ada jenis-jenis pertanyaan yang perlu dihindari (lihat Kotak 5.3). Tujuan kita bertanya adalah menarik keluar informasi tentang pengalaman tertentu dari orang yang mengalaminya
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup82
langsung. Dengan mewawancarai orang yang bekerja sebagai ekspatriat di Indonesia, misalnya, kita menarik keluar informasi tentang pengalaman orang yang punya pengalaman langsung sebagai ekspatriat di Indonesia. Penelitian fenomenologis berjalan dalam semangat epochē. Wawancara perlu menunjukkan epochē itu. Pertanyaan yang mencerminkan epochē adalah pertanyaan yang netral dan memberi kebebasan pada partisipan untuk mengungkapkan pengalamannya. Untuk menjaga epochē dalam bertanya, pertanyaan-pertanyaan dalam kotak berikut perlu dihindari.
Kotak 5.3 Pertanyaan-pertanyaan yang Perlu Dihindari
1. Pertanyaan-pertanyaan dengan empati berlebihan (over-empathic questions), yaitu pertanyaan yang mengklaim memahami betul perasaan atau emosi partisipannya dan mengajak partisipan setuju dengan perasaannya. Misalnya, “Saya bisa merasakan betapa sakitnya diabaikan seperti itu, seperti itukan yang kamu rasakan?”
2. Pertanyaan-pertanyaan yang memanipulasi patisipan (manipulative questions), yaitu pertanyaan yang secara lihai mendorong partisipan untuk memberi jawaban yang diinginkan peneliti. Misalnya, “Tadi Anda mengatakan bahwa Anda merasa diabaikan. Bukankah kenyataannya lebih buruk daripada itu?”
3. Pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan (leading questions), yaitu pertanyan yang memaksa partisipan untuk memberi jawaban yang diinginkan. Misalnya, “Pasti sakit sekali rasanya diabaikan seperti itu?”
4. Pertanyaan-pertanyaan (closed questions), yaitu pertanyan yang hanya dijawab dengan “ya”, “tidak”, atau informasi singkat yang tidak mencerminkan pengalaman. Misalnya, “Anda sudah dua tahun menikah, kan?”
Pertanyaan-pertanyaan di atas adalah pertanyan-pertanyaan yang tidak men cerminkan epochē dalam penelitian fenomenologis. Semua pertanyaan itu adalah pertanyaan nonfenomenologis yang mengandung prasangka. Nah, semakin jelas sekarang bahwa peneliti perlu menjaga dirinya sendiri saat bertanya dan selalu fokus pada partisipan sembari membebaskan partisipan untuk bercerita tentang pengalaman hidupnya. Semakin banyak kesempatan kepada partisipan untuk menceritakan pengalamannya, semakin baik. Mari
BAB V Persiapan ke Lapangan:Literatur dan Pengumpulan Data 83
kita lihat lagi beberapa contoh panduan wawancara yang tersedia dalam Kotak 5.4.
Kotak 5.4 Contoh-contoh Panduan Wawancara
Pengalaman Wanita yang Direhabilitasi karena Kecanduan Pnina Shinebourne dan Jonathan Smith
1 Bisa ceritakan peran alkohol/drugs dalam hidup Anda saat ini?
Prompt yang mungkin: Apa yang terjadi? Apa yang kamu rasakan? Bagaimana kamu mengatasinya?
2 Bisa ceritakan terakhir kali Anda mengonsumsi alkohol/drugs?
Prompt yang mungkin: Apa yang terjadi? Apa yang kamu rasakan? Bagaimana kamu mengatasinya?
3 Bisa ceritakan bagaimana alkohol/drugs itu memengaruhi hubunganmu dengan orang lain?
Prompt yang mungkin: sahabat, teman, keluarga, teman kampus/kerja?
4 Bisa ceritakan bagaimana awal mula Anda mengonsumsi alkohol/drugs?
Prompt yang mungkin: Kapan persisnya itu? Apa dampaknya bagi Anda? Bisa ceritakan seperti apa perasaan Anda saat itu?
5 Apakah ada perubahan dalam cara Anda mengonsumsi alkohol/drugs dari waktu ke waktu?
Prompt yang mungkin: Perubahan seperti apa? Apakah membaik? Apakah memburuk? Apa yang Anda rasakan tentang perubahan itu?
6 Perkembangan positif apa yang Anda harapkan terjadi?
Prompt yang mungkin: Bagaimana kondisi Anda bisa membaik? Bisa Anda bayangkan seperti apa kondisi yang baik itu.
7 Bagaimana Anda menggambarkan pribadi Anda?
Prompt yang mungkin: Apa yang kamu rasakan tentang dirimu sendiri?
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup84
8 Apakah masalah alkohol/drugs ini sudah mengubah pikiran dan perasaan tentang dirimu sendiri?
Prompt yang mungkin: Apakah kamu melihat dirimu sekarang sudah berbeda dibandingkan dulu sebelum ada masalah alkohol/drugs ini? Dalam hal apa saja?
9 Bagaimana menurutmu pandangan orang-orang tentangmu?
Prompt yang mungkin: Teman, sahabat, keluarga, teman kampus kerja?
10 Bagaimana kamu melihat dirimu di masa depan?
Komentar: Ada sepuluh pertanyaan dalam panduan wawancara di atas. Pertanyaan-pertanyaan dalam panduan wawancara tidak harus sebanyak itu. Tujuan kita membuat panduan wawancara adalah mengajukan pertanyaan dan membiarkan partisipan bercerita sembari mendorongnya bercerita lebih banyak lewat prompt. Perhatikan lagi contoh panduan wawancara dengan lima pertanyaan pokok berikut:
Pengalaman Cuci Darah (Dialisis)
1 Bisa ceritakan secara singkat riwayat gangguan ginjal Anda hingga akhirnya Anda harus cuci darah?
2 Menurut Anda secara pribadi, apa yang terjadi saat cuci darah?
3 Apa yang Anda rasakan saat Anda sedang menjalani cuci darah?
Prompt yang mungkin: Secara fisik? Secara emosional? Secara mental?
4 Bagaimana cuci darah/masalah ginjal Anda memengaruhi kehidupan Anda sehari-hari?
Prompt yang mungkin: Dalam pekerjaan, minat, hubungan atau relasi dengan orang lain?
5 Jika Anda diminta untuk menggambarkan apa artinya mesin cuci darah, apa yang Anda katakan?
Prompt yang mungkin: Kata-kata apa yang terpikir tentang mesin itu? Apakah ada nama khusus yang anda ingin berikan untuk mesin itu?
Komentar: Prompt menjadi alat bantu untuk memperdalam informasi agar pertemuan dengan partisipan benar-benar mencerminkan wawancara yang mendalam (in-depth interview). Masih ada satu contoh panduan wawancara lagi yang akan menunjukkan jumlah pertanyan yang sedikit dengan prompt yang banyak.
BAB V Persiapan ke Lapangan:Literatur dan Pengumpulan Data 85
Perilaku Sakit Kelompok Etnis Minoritas Tibet di India UtaraIgor Pietkiewicz & Jonathan A. Smith
1 Bisa ceritakan pengalaman sakit Anda selama di pengasingan?
Prompt yang mungkin: Masalah-masalah kesehatan apa yang Anda alami? Bagaimana rasanya di badan Anda? Gejala-gejala apa yang Anda rasakan? Apa artinya gejala-gejala itu? Menurutmu, kenapa gejala-gejala itu muncul pada waktu itu? Apa yang muncul dalam pikiranmu (asosiasi apa atau fantasi apa yang muncul)?
2 Apa yang membuatmu bisa merasa lebih ringan atau lebih baik pada waktu itu?
Prompt yang mungkin: Perawatan apa yang Anda anggap sangat cocok pada waktu itu? Kenapa? Apa yang menurutmu sebaiknya dilakukan untuk membantu kesembuhanmu? Jika tidak ada perawatan atau penanganan pada waktu itu, seperti apa kondisimu?
3 Bagaimana reaksi awal Anda dan reaksi lanjutan Anda pada waktu itu?
Prompt yang mungkin: Bagaimana Anda memutuskan untuk mencari bantuan untuk masalah kesehatanmu? Di mana Anda mencari bantuan? Apa yang menghambat Anda mencari bantuan? Jika partisipan mendapat penanganan medis/nonmedis: bagaimana pendapatmu tentang saran-saran yang diberikan? Apakah ada kemiripan atau perbedaan antara apa yang Anda pikirkan tentang penyakit Anda dan saran-saran yang Anda terima dari orang yang mengobati Anda?
Seperti itulah maksud dari penyusunan panduan wawancara. Kita menyusun pertanyaan-pertanyaan pokok sambil menyiapkan prompt. Prompt itu sangat bermanfaat untuk mengantisipasi macam-macam informasi yang perlu digali. Tentu saja semua prompt tidak perlu ditanyakan bila sudah ada kejelasan saat partisipan bercerita. Karena itu, peneliti perlu menjadi pen-dengar yang aktif (active listener).
Panduan wawancara sangat menentukan berhasilnya wawancara semi-terstruktur. Dalam penelitian fenomenologis, peneliti pemula disarankan melakukan wawancara semi-terstruktur. Seiring dengan bertambahnya jam terbang, peneliti akan memiliki keterampilan mewawancarai yang semakin matang sehingga wawancara semi-terstruktur bisa digeser menjadi wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup86
cukup mengawali wawancara dengan pertanyaan kunci. Anda bisa memulai wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan berikut.
• Apa artinya menjalani rehabilitasi narkoba ini buatmu? • Apa artinya pengalaman cuci darah ini buat Anda? • Apa artinya sakit dalam pengasingan buat Anda?
Setelah mengajukan pertanyaan pokok itu, peneliti menjaga agar komunikasi berkembang tanpa lari dari topik dan tujuan penelitian. Begitu pertanyaan selesai diajukan, peneliti menjadi pendengar aktif yang penuh perhatian menyimak sekaligus memperdalam informasi yang dirasakan kurang, belum jelas, atau belum lengkap.
D. Panduan Wawancara dalam PFD
Pembicaraan kita tentang panduan wawancara di atas adalah panduan yang umum digunakan dalam IPA. Bagaimana dengan panduan wawancara dalam PFD? Sebenarnya poin-poin panduan wawancara dalam IPA di atas bisa juga diterapkan dalam PFD. PFD juga menggunakan wawancara semi-terstruktur untuk peneliti yang belum berpengalaman dan wawancara tak-terstruktur untuk peneliti yang sudah berpengalaman. Pedoman pokok yang ditonjolkan Giorgi (2009:123) adalah saat melakukan wawancara, peneliti tidak leading partisipannya, tetapi directing partisipannya. Leading berarti menjadi orang yang kemauannya diikuti; sementara directing berarti menjadi orang yang mengarahkan partisipan agar tidak melenceng dari fokus penelitian.
Dalam PFD kita mengajukan pertanyaan yang bertujuan mendorong partisipan untuk mendeskripsikan pertanyaan. Oleh karena itu, pertanyaan pokok dalam PFD adalah ajakan atau permintaan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan pengalaman. Englander (2012:26), misalnya, menulis sebagai berikut.
BAB V Persiapan ke Lapangan:Literatur dan Pengumpulan Data 87
Teks Asli
The first question one should ask to the participant is: Can you please describe as detailed as possible a situation in which you experienced “a phenomenon”. If we had the general psychological phenomenon of emotional memory, for example, we would ask the participant: Can you describe a situation in which you remembered something emotional. The remaining questions should follow the response of the interviewee with a focus on the phenomenon being researched.
Transkreasi
Pertanyaan pertama yang sebaiknya diajukan peneliti PFD kepada partisi pannya adalah: Bisakah Anda menggambarkan serinci mung kin situasi di mana Anda mengalami “....... (fenomena tertentu, misal nya pengalaman sembuh dari keter gan-tungan alkohol)”. Jika penelitian kita terkait dengan fenomena psiko-logis tertentu berupa ingatan yang emosional, misalnya, maka kita bisa bertanya kepada partisipan: Bisa gam barkan situasi di mana Anda mengingat peristiwa itu secara emosional? Pertanyaan-pertanyaan beri kutnya akan mengikuti jawaban yang diberikan oleh partisipan dan peneliti hanya perlu berfokus pada fenomena yang sedang diteliti.
Perhatikan pertanyaan kuncinya adalah, “Bisa gambarkan/deskripsikan ... ?” Sesudah itu Anda menjadi pendengar yang aktif dan empatetik. Bila ada sesuatu yang tidak jelas, tanyakan lebih jauh. Gunakan pertanyaan-pertanyaan netral yang sudah kita bicarakan di atas. Dalam PFD, dikenal dua cara mengajukan pertanyaan dalam wawancara, yaitu (1) pertanyaan yang dijawab langsung secara verbal dan (2) pertanyan yang dijawab secara tertulis atau direkam tanpa pertemuan langsung. Silakan memilih yang Anda sukai sejauh tujuan PFD tercapai, yaitu mendapatkan gambaran (deskripsi) selengkap mungkin tentang fenomena tertentu yang dialami partisipan. Berikut ini contoh wawancara untuk jawaban tertulis.
Saya berterima sekali untuk kesediaan Anda berpartisipasi dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman Anda sembuh dari kecanduan alkohol. Semua informasi yang Anda berikan hanya diketahui oleh saya (Amalia, Fakultas Psikologi
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup88
Universitas Diponegoro) dan dijaga kerahasiaannya. Sebelum penelitian ini dibaca oleh orang lain atau dipublikasikan, saya akan menyamarkan identitas Anda.
Bisa gambarkan pengalaman Anda sembuh dari kecanduan alkohol? ........................Tantangan dan dukungan apa yang Anda dapatkan dan proses lepas dari kecanduan alkohol? ........................
Wawancara tertulis seperti itu tampaknya menarik bagi masyarakat digital sekarang ini. Mahasiswa boleh saja melakukannya. Bagaimanapun, harus diakui bahwa wawancara yang tidak bertemu langsung atau dimediasi komputer akan kehilangan banyak nuansa halus, seperti ucapan yang spontan dan ekspresi tubuh. Dalam lingkungan akademis Barat, Mahasiswa S1 sebagai peneliti pemula tampaknya mendapat toleransi melakukan wawancara tidak langsung yang dimediasi komputer itu. Englander (2012:27), misalnya, menulis sebagai berikut.
Teks Asli
The face-to-face interview is often longer and thus richer in terms of nuances and depth. The shorter written descriptions are useful for undergraduate research projects or workshop material. Although one could extend the amount of subjects in collecting shorter description (for the sake of practicing using the method) to compensate for the flavor of the many nuances usually gained in the longer face-to-face interview.
Transkreasi
Wawancara langsung sering kali lebih lama dan lebih kaya dalam hal nuansa-nuansa dan kedalaman wawancara. Deskripsi tertulis yang lebih singkat bermanfaat untuk proyek-proyek penelitian mahasiswa S1 atau materi workshop (pelatihan). Tujuannya adalah untuk berlatih menggunakan metode. Kekurangan nuansa dan kedalaman informasi dalam wawancara tertulis umumnya diatasi dengan memperbanyak jumlah subjek.
Saya kira, mahasiswa bisa dituntut lebih daripada itu. Peneliti S1 bukan sekadar belajar menggunakan metode, tetapi juga belajar bertemu orang dan merasakan nuansa-nuansa halus dalam pertemuan itu. Untuk
BAB V Persiapan ke Lapangan:Literatur dan Pengumpulan Data 89
lingkungan budaya masyarakat Indonesia, pertemuan langsung bukan sesuatu yang menjadi kesulitan. Sejauh ini, meski punya keterbatasan dalam mengembangkan wawancara, mahasiswa-mahasiswa S1 yang saya temui tidak memiliki kesulitan dalam bertemu langsung partisipan. Masalah mereka lebih pada kesulitan membangun rapport dan mengatasi rasa canggung saat wawancara. Dalam pertemuan langsung itu, mereka tidak hanya belajar menerapkan metode penelitian fenomenologis, tetapi juga melatih merasakan diri sendiri dan partisipannya selama wawancara. Jadi, wawancara langsung tetap perlu untuk mahasiswa tingkat S1. Kita hanya perlu menoleransi level kedalaman wawancara untuk peneliti pemula yang masih belajar merasa tenang saat wawancara.
Sebelum melangsungkan wawancara penelitian, peneliti PFD kadang-kadang mengadakan pertemuan pra-wawancara yang bisa dilakukan seminggu sebelum wawancara penelitian. Manfaat utama dari rapport adalah mengupayakan keterbukaan partisipan untuk memberi informasi kepada peneliti. Pertemuan pra-wawancara juga bermanfaat bagi peneliti untuk menjelaskan niat dan tujuan penelitiannya. Dalam pertemuan pertama ini, peneliti bisa menunjukkan consent form (lembar persetujuan) untuk ditandatangani oleh partisipan sehingga dalam petemuan selanjutnya peneliti dan patisipan bisa langsung masuk ke dalam wawancara. Paling tidak, seperti itulah prosedur umum dilakukan oleh peneliti-peneliti fenomenologis dalam lingkungan akademis Barat.
E. Jumlah Partisipan dalam IPA
Panduan wawancara dibuat untuk dijadikan acuan saat bertanya kepada partisipan. Pertanyaan yang paling sering diajukan oleh peneliti pemula adalah berapa jumlah partisipan dalam IPA? Akademisi yang terbiasa melakukan penelitian kuantitatif dengan sampel besar kerap mempertanyakan jumlah partisipan yang sedikit dalam penelitian kualitatif. Dalam IPA memang dikemukakan dengan jelas tentang perlunya small sample size (ukuran sampel yang kecil). Artinya, jumlah partisipannya memang sedikit jika dibandingkan dengan penelitian kuantitatif yang bisa mencapai ratusan sampel, bahkan ribuan. Tentang penjelasan small sample size ini, saya kutip langsung per-nyataan Jonathan A. Smith dkk. (2009: 51-52).
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup90
Teks Asli
As a rough guide, we would suggest that between three and six participants can be a reasonable sample size for a student project using IPA. Indeed many studies by experienced IPA researchers now have numbers in this range. This should provide sufficient cases for the development of meaningful points of similarity and difference between participants, but not so many that one is in danger of being overwhelmed by the amount of data generated. In effect, it is more problematic to try to meet IPA’s commitments with a sample which is ‘too large’, than with one that is ‘too small ’.
Our own practice is now to treat n = 3 as the default size for an undergraduate or Master-level IPA study. Three is a very useful number. It allows one to conduct a detailed analysis of each case – in effect, to develop three separate case studies – but it them also allows for the development of a subsequent micro-analysis of similarities and differences across cases. For example, how is case A different to case B? How are cases A and B different from C? How are all three cases similar?
Transkreasi
Sebagai panduan kasar, kami menyarankan bahwa jumlah partisipan yang berkisar antara 3 dan 6 adalah jumlah sampel yang bisa diterima un-tuk proyek penelitian mahasiswa yang menggunakan IPA. Memang saat ini, ada banyak penelitian yang dijalan kan oleh peneliti IPA yang sudah berpe-ngalaman memiliki jumlah sampel dalam rentang ini (3-6). Jumlah ini seharusnya sudah cukup untuk me-lihat kemiripan dan perbedaan di antara partisipan. Jumlah partisipan yang banyak riskan membuat peneliti keban jiran data. Oleh karena itu, ada lebih banyak masalah dalam menjalan-kan IPA dengan jumlah sampel yang “terlalu besar” ketimbang dengan jumlah sampel yang “terlalu kecil”.
Dalam praktik yang kami jalankan saat ini, jumlah 3 partisipan adalah ukuran sampel yang bisa digunakan untuk penelitian level S1 atau S2. Tiga adalah jumlah yang sangat ber-manfaat. Jumlah itu membuat pene-liti bisa melakukan analisis yang menda lam untuk masing-masing kasus (pengalaman partisipan). Analisis per kasus ini bisa berdampak pada pengembangan tiga penelitian kasus (pengalaman partisipan). Di samping itu, jumlah 3 juga membantu pengembangan mikro-analisis (analisis
BAB V Persiapan ke Lapangan:Literatur dan Pengumpulan Data 91
yang detail) tentang kemiripan dan perbedaan di antara partisipan-partisipan. Sebagai contoh, bagaimana kasus (pengalaman) A berbeda dari kasus (pengalaman) B? Bagaimana kasus A dan B berbeda dari kasus C? Bagaimana kemiripan ketiga kasus?
Ada kalanya kita menemui kasus yang sangat unik di mana jumlah partisipannya lebih kecil lagi. Untuk kasus yang sangat unik ini, jumlah satu partisipan dibolehkan sejauh peneliti bisa meyakinkan bahwa jumlah satu partisipan itu adalah jumlah maksimal yang memang tersedia bagi peneliti. Untuk analisis kasus unik seperti itu, peneliti pemula tidak disarankan untuk melakukannya. Kasus unik dan tunggal butuh penggalian informasi yang dalam pada satu orang. Penggalian yang dalam itu sebaiknya dilakukan oleh peneliti yang sudah berpengalaman.
Istilah lain untuk ketersediaan partisipan ini adalah aksesibilitas par-tisipan. Jadi, pertanyaan penting dalam menentukan jumlah partisipan adalah berapa jumlah partisipan yang bisa diakses oleh peneliti? Jawabannya didapatkan setelah peneliti mencoba melakukan survei pendahuluan di lapangan. Jika yang tersedia banyak, jumlah 3-6 adalah jumlah yang ideal untuk mahasiswa level S1 atau mahasiswa level S2 dan lebih dari 6 adalah jumlah yang ideal untuk mahasiswa level S3.
Jadi, small sample size (ukuran sampel yang kecil) membawa tanggung jawab yang besar, yaitu peneliti menjalankan wawancara yang mendalam (in-depth interview). Peneliti menggali informasi tentang pengalaman partisipan sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya. Ada yang mengatakan bahwa hasil wawancara yang baik menujukkan minimal 90% ucapan partisipan dan maksimal 10% pertanyaan peneliti. Persentase seperti itu boleh saja dijadikan acuan, tetapi intinya begini.
• Hasilwawancarayangbaikmemperlihatkanbahwapartisipanba-nyak bercerita tentang pengalaman pribadinya.
• Agar partisipan banyak bercerita, partisipan harus merasa enak/nyaman bercerita di depan peneliti.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup92
• Untuk enak/nyaman bercerita di depan peneliti, peneliti harusme nunjukkan diri sebagai pribadi yang dipercaya untuk diajak bercerita.
• Upayapenelitiuntukmenunjukkandirinyasebagaipribadiyangbisadipercaya oleh partisipan disebut rapport building (pembentukan kepercayaan).
Poin yang terakhir itu penting sekali: peneliti perlu membangun rapport yang baik. Istilah rapport berasal dari kata Prancis le rapport yang artinya “trust (kepercayaan)”. Membangun rapport berarti membangun kepercayaan dalam hubungan antara peneliti dan partisipan. Jika rapport (kepercayaan) dalam hubungan peneliti-partisipan belum terbentuk dengan baik, saya sarankan untuk tidak terburu-buru melakukan wawancara. Cairkan dahulu situasinya sampai partisipan terlihat relaks untuk bercerita. Ada seorang mahasiswa yang memiliki calon partisipan yang cukup banyak. Sayangnya, rapport yang terbentuk belum baik sehingga beberapa partisipan harus digugurkan karena jawaban-jawaban yang mereka berikan sekadarnya saja dan masih menunjukkan resistensi (kendala dalam mengekspresikan pengalaman).
F. Jumlah partisipan dalam PFD
Jumlah sampel dalam PFD juga tidak menuntut sampel besar. Giorgi (2009) menekankan bahwa penelitian kualitatif tidak repot dengan strategi sampling, tetapi repot dengan strategi kedalaman analisis. Dalam penelitian kuantiatif, strategi sampling sangat penting karena hasil analisis data yang didapatkan dari sampel-sampel akan digeneralisasikan pada populasinya. Hubungan sampel dan populasi itu bisa diibaratkan dengan mengambil segenggam beras (sampel) dari sekarung beras (populasi) untuk mendapat gambaran menyeluruh (generalisasi) tentang seluruh beras dalam karung. Teknik pengambilan sampel yang tidak tepat bisa berdampak pada kesulitan untuk generalisasi.
Penelitian fenomenologis tidak mengenal generalisasi, bahkan tidak punya niat untuk melakukan generalisasi. Ada satu artikel dari Magnus Englander (2012) yang berjudul “The Interview: Data Collection in Descriptive Phenomenological Human Scientific Research (Interviu: Pengumpulan Data dalam Penelitian Ilmiah untuk Manusia dengan Menggunakan Penelitian
BAB V Persiapan ke Lapangan:Literatur dan Pengumpulan Data 93
Fenomenologis Deskriptif )”. Dalam artikel itu, Englander (2012:21) menulis tentang bagaimana menentukan jumlah partisipan dalam PFD.
Teks Asli
The phenomenological method in human science recommends that one uses at least three participants, obviously not because that the number three corresponds with a statistical analysis but because one or two subjects would be too difficult for the researcher to handle in terms of their own imagination (Giorgi, 2009). Although we are not interested in “how many?” who have had a particular experience, for the purpose of comparison, we could take note on how many times the phenomenon makes its presence in the description (Giorgi, 2009, p. 198). As Giorgi (2009, pp. 198–199) points out, “Research based upon depth strategies should not be confused with research based upon sampling strategies.” Hence, one could also use five or twenty participants for that matter; however, it would most likely mean more work for the researcher and better appreciation for variation of the phenomenon, rather than better generality of the results.
Transkreasi
Metode fenomenologis [deskriptif ] dalam ilmu kemanusiaan merekomen-dasikan bahwa peneliti menggunakan paling sedikit 3 partisipan. Tentu saja jumlah 3 ini tidak ada kaitannya dengan analisis statistis. Bila partisipan hanya berjumlah 1 atau 2, peneliti akan kesulitan menganalisis pengalaman yang beragam. Meskipun kita tidak tertarik dengan “berapa banyak” orang yang mengalami pengalaman tertentu, kita perlu membuat perbandingan dengan memperhatikan berapa kali fenomena (peristiwa/kejadian mental) tertentu muncul saat mendeskripsikan pengalaman semua partisipan. Sebagaimana yang dikatakan Giorgi, “Penelitian yang didasarkan pada strategi kedalaman [penelitian kualitatif-fenomenologis] jangan dikacaukan dengan penelitian yang didasarkan pada strategi sampling [penelitian kuantitatif ]”. Oleh karena itu, peneliti boleh saja menggunakan 5 atau 20 partisipan; tetapi dengan menggunakan jumlah yang besar, peneliti perlu bekerja lebih keras dan lebih menghargai variasi fenomena (peristiwa/kejadian mental) dalam pengalaman partisipan ketimbang memperhatikan bagaimana menggeneralisasikan hasil penelitian.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup94
Saya kira sudah jelas bahwa kita tidak bisa menentukan jumlah persis untuk partisipan dalam penelitian fenomenologis. Dalam tulisan di atas, ada penekanan pada jumlah “paling sedikit 3” untuk PFD. Tujuannya adalah peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena yang muncul dari beberapa partisipan. Membandingkan di sini berarti bisa melihat kemiripan dan perbedaan di antara partisipan-partisipan. Pada akhirnya, peneliti PFD diharapkan bisa menampilkan esensi dari pengalaman partisipan. Jadi, peneliti boleh saja memiliki jumlah partisipan 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya dengan konsekuensi bahwa semakin besar jumlah sampel, semakin kuat komitmen menjalankan analisis untuk data yang besar.
Masih ada satu lagi panduan yang juga bisa membantu kita dalam menentukan jumlah sampel, yaitu aksesibilitas peneliti. Aksesibilitas berarti kemampuan peneliti untuk mengakses atau menjangkau partisipan. Ada penelitian dengan partisipan yang sulit diakses sehingga jumlah 3 partisipan sudah maksimal dan ada penelitian dengan partisipan yang mudah diakses sehingga jumlah 3 partisipan dianggap masih kurang. Sebagai contoh, seorang peneliti pernah tertarik meneliti ayam kampus (istilah lokal untuk mahasiswi tunasusila). Dia mengatakan kepada saya, “Ada cukup banyak kok Pak”. Saya menyarankannya melakukan survei pendahuluan untuk tahu apakah mereka bersedia diwawancarai. Dia lalu kembali lagi dan bercerita tentang kesulitannya menemukan partisipan yang bersedia diwawancarai. Hanya ada satu yang bersedia. Jadi, pertanyaannya bukan “berapa banyak yang harus ada?”, tetapi “berapa banyak yang bisa diakses/dijangkau oleh peneliti?” Demikianlah, jumlah sampel ditentukan oleh komitmen peneliti untuk menganalisis data plus aksesibilitas peneliti.
95
BAB VI
Persiapan ke Lapangan: Menjelang Wawancara
A. Wawancara yang Eksploratif
Dengan memiliki panduan wawancara dan rapport yang baik, peneliti siap untuk turun ke lapangan dan bertemu dengan partisipan. Pada tahap ini, peneliti mengembangkan harapan bahwa pertemuannya dengan partisipan/subjek penelitian akan berjalan lancar. Keberhasilan peneliti menarik informasi selama wawancara berlangsung terkait erat dengan kemampuan berkomunikasi, khususnya kemampuan bertanya dan mendengarkan secara empatetik.
Mendengarkan secara empatetik berarti menyimak jawaban-jawaban yang diberikan partisipan dengan mencoba setepat mungkin merasakan apa yang mereka, mencoba memikirkan setepat mungkin apa yang mereka pikirkan, mencoba membayangkan setepat mungkin apa yang mereka bayangkan. Dalam kutipan yang mengawali buku ini, saya mengutip pernyataan Carl Rogers tentang pentingnya mendengarkan secara empatetik. Untuk sekadar menyegarkan ingatan, saya kembali menampilkannya di sini.
“Setiap hal penting yang saya ketahui tentang manusia, yang saya pelajari dari mereka, adalah mendengarkan mereka, mencoba ikut merasakan hidup mereka dari dalam, tanpa mengadili atau menilai mereka, hanya mencoba ikut merasakan setepat mungkin, bagaimana sebenarnya pribadi ini menghayati hidupnya saat ini.”
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup96
Saat kita mendengarkan secara empatetik kita akan menjadi lebih sensitif dengan aliran informasi yang mengalir dari pengalaman partisipan kita. Sensitivitas ini akan mendorong kita untuk paham lebih dalam dengan bertanya lebih jauh tentang apa yang mereka pikiran dan rasakan tanpa menilai atau mengadili mereka. Dalam mendengarkan secara empatetik, kita sebenarnya mempraktikkan epochē. Kita menyingkirkan penilaian kita dan berfokus pada dunia pengalaman partisipan kita. Nah, sikap mental seperti ini perlu dikembangkan dan diniatkan untuk dijalankan selama wawancara.
Selain persiapan pribadi seperti itu, peneliti perlu juga memeriksa alat-alat penunjang, seperti alat perekam. Beberapa mahasiswa bercerita bahwa partisipan menunjukkan ketidaknyamanan saat direkam sehingga mereka terlihat tegang selama wawancara. Kita sebaiknya bersikap genuin atau jujur kepada partisipan pada saat ingin merekam dengan mengatakan demikian:
“Sebelum kita memulai wawancara ini, saya ingin berterus terang bahwa hasil wawancara ini akan saya ketik nantinya. Saya merasa kesulitan bila harus mencatat apa yang akan Anda ceritakan nantinya. Oleh karena itu, saya perlu izin Anda untuk merekam percakapan kita ini. Saya akan menjaga kerahasiaannya. Identitas Anda juga akan disamarkan. Ada saatnya nanti, setelah selesai mengetik dan memeriksa hasil wawancara, rekaman ini akan dimusnahkan.”
Dalam mengumpulkan data, seorang peneliti fenomenologis sebenarnya berharap mendapatkan jawaban yang mendalam tentang pengalaman par-tisipannya. Semakin banyak laporan pengalaman partisipan, semakin baik bahan-baku yang dimiliki peneliti untuk diolah atau dianalisis. Saat satu pertanyaan selesai diajukan, peneliti tidak perlu tergesa-gesa meloncat ke pertanyaan berikutnya. Begitu pertanyaan diajukan, dengarkan partisipan dengan aktif dan empatetik.
• Bila ada pernyataan yang Anda tidak dimengerti, tanyakan agarAnda mengerti. Misalnya: Tadi Anda mengatakan “....”. Bisa jelaskan lebih jauh maksudnya?
• Kalau ada istilah yang membingungkan Anda, tanyakan supayaAnda tidak lagi bingung. Misalnya: Anda tadi menyebutkan “...”, maksudnya apa yah?
BAB VI Persiapan ke Lapangan:Menjelang Wawancara 97
• Kalauadapernyataanyangkuranglengkap,tanyakanbiarpernyataanmenjadi lebih lengkap. Misalnya: Menarik sekali yang Anda katakan tentang .... Bisa ceritakan lebih jauh tentang itu?
Nah, setelah satu pertanyaan pokok dalam panduan wawancara dirasakan cukup, silakan pindah ke pertanyaan berikutnya. Begitu seterusnya. Silakan kreatif mengajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang mendorong partisipan untuk bercerita semakin banyak dan dalam.
Melangsungkan wawancara adalah pengalaman yang ditunggu-tunggu oleh peneliti sekaligus membuat was-was. Mahasiswa yang telah menye-lesaikan rancangan (draft) penelitiannya sampai pada panduan wawancara biasanya cukup bersemangat bertanya: “Pak, saya sudah boleh wawancara?” Secara subjektif, mahasiswa mungkin sudah merasa siap. Bagaimanapun, kita perlu mencegah ketergesa-gesaan yang membuat hasil tidak maksimal. Untuk memantapkan kesiapan-diri itu, lima pertanyaan berikut bisa menjadi alat bantu.
1. Sudahkah saya melihat disposisi/kecenderungan dalam diriku yang poten sial menganggu netralitasku?
Kita memeriksa diri untuk mengetahui seberapa bebas diri kita dari asumsi dan penilaian-penilaian yang bisa mengganggu ketulusan kita dalam mendengarkan pengalaman partisipan. Nah, kita kembali berbicara tentang epochē. Saat wawancara berlangsung, peneliti perlu mengawasi diri sendiri dari kecenderungan menilai atau mengadili orang lain. Dalam wawancara, kita tidak mencari jawaban yang kita inginkan dari partisipan. Sebagai peneliti fenomenologis, kita dalam posisi tidak tahu dan ingin diberi tahu tentang pengalaman partisipan.
2. Apakah partisipan yang saya wawancara memenuhi syarat?
Intinya, kita tidak keliru dalam memilih partisipan. Apa gunanya wawancara panjang-lebar jika partisipan bukan orang yang tepat untuk diwawancarai. Agar tidak keliru dalam mewawancarai par-tisipan, buatlah karakteristik partisipan penelitian Anda. Ada se-orang mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang penga-laman penderita gangguan mental yang disebut gangguan bipolar.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup98
Saya lalu bertanya, “Bagaimana kamu tahu dia mengalami bipolar?” Saya diberi jawaban, “Ada komunitasnya yang saya temukan lewat internet”. Tidak lama berselang, saya diminta untuk mengisi kon-seling kelompok untuk calon-calon partisipan itu. Dalam sesi konseling, saya menanyai mereka tentang pengalaman mereka didiag nosis bipolar. Beberapa dari mereka mengaku hanya merasa bipolar berdasarkan bacaan mereka di mesin pencari Google. Jelas sekarang bahwa beberapa partisipan dalam komunitas bipolar itu hanya merasa bipolar dan bukan didiagnosis bipolar. Saya menyaran-kan untuk menemukan partisipan yang homogen. Artinya, semua partisipan seharusnya didiagnosis bipolar.
3. Apakah partisipanku benar-benar bersedia untuk berpartisipasi?
Kadang-kadang suasana hati partisipan atau suasana lokasi wawan-cara tidak seperti yang diharapkan oleh peneliti. Partisipan bisa saja resisten atau belum bisa terbuka sepenuhnya untuk menceritakan pengalamannya. Dampaknya, jawaban partisipan menjadi singkat dan sekadarnya. Beberapa mahasiswa melaporkan bahwa ada par-tisipan yang meminta ganjaran untuk informasi yang akan diberikan, ada yang meminta ditemani oleh orang lain, ada juga yang meminta bantuan orang dekat untuk ikut menjawab, bahkan ada yang berubah pikiran dan membatalkan wawancara. Semua itu terjadi karena ke-gagalan membangun rapport (kepercayaan). Oleh karena itu, jauh lebih baik meluangkan waktu untuk membangun rapport dengan hasil yang memuaskan daripada tergesa-gesa wawancara dengan hasil yang tidak memuaskan. Ciri dari rapport yang baik adalah partisipan merasa leluasa dan relaks bercerita tentang pengalamannya selama wawancara.
4. Perlengkapan apa saja yang saya perlukan dalam wawancara?
Perlengkapan administratif yang diperlukan. Kamera, rekaman, lem-bar informasi (information sheet), dan lembar persetujuan (consent form). Siapkan apa saja yang dibutuhkan secara adminsistratif sehingga peneliti tidak harus memboroskan waktu kembali ke la-pangan untuk melengkapi kekurangan. Pertanyaan-pertanyaan beri-kut bisa dijadikan alat bantu sebelum ke lapangan.
BAB VI Persiapan ke Lapangan:Menjelang Wawancara 99
a. Apakah panduan wawancaraku sudah bersih dari dari per-tanyaan-pertanyan yang leading, tertutup, dan manipulatif ?
b. Apakah saya sudah yakin dengan alat perekam saya? Bagaimana dengan sensitivitasnya menangkap suara? Apakah saya perlu menyiapkan cadangan?
c. Apakah saya sudah membawa lembar informasi penelitian saya untuk dibaca sebelum wawancara?
d. Apakah saya sudah membawa lembar persetujuan?
B. Frekuensi Wawancara dalam IPA dan PFD
Saya sering kali mendapat pertanyaan tentang berapa kali peneliti harus mewawancarai satu partisipan. Apakah satu kali cukup? Atau harus lebih dari sekali? Tidak ada panduan tentang berapa kali wawancara harus dijalankan. Yang ada hanyalah apakah pertanyaan-pertanyaan peneliti sudah mendapatkan jawaban yang mencerminkan informasi yang dalam. Dalam penelitian fenomenologis, kita menjalankan in-depth inteview, yaitu wawancara yang bukan sekadar mendapatkan informasi, tetapi juga menggali informasi yang didapatkan. Wawancara bisa dijalankan sekali dan bisa juga dijalankan lebih dari sekali. Tidak ada kepastian menyangkut jumlah.
Saya pernah meminta bantuan tukang untuk membuatkan tandon bawah di halaman depan rumah saya. Menurutnya, waktu seminggu cukup baginya untuk menyelesaikan. Saat memulai pekerjaan, saya mendapat laporan bahwa tanah di sekitar rumah saya tanah wadas. Saya menyaksikan sendiri kesulitan yang mereka alami. Pengalaman serupa bisa terjadi dalam pengumpulan data. Peneliti merasa siap dengan dengan rapport dan panduan wawancara yang sudah baik sehingga dia merasa wawancara cukup satu kali. Bagaimanapun, situasi lapangan kadang-kadang menuntut kita mengubah perencanaan awal.
Sejauh ini, kita sudah mengenal dua versi penelitian fenomenologis yang berkembang dalam psikologi, yaitu PFD dan IPA. Dalam PFD, kita sering kali mendapat pernyataan tegas bahwa wawancara harus lebih dari
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup100
sekali. Permintaan itu bisa dimengerti karena wawancara pertama sering kali belum menunjukkan rapport yang baik sehingga diperlukan wawancara lanjutan (follow-up interview) untuk menggali informasi yang lebih dalam dari partisipan.
Dalam IPA, jumlah wawancara sekali bukan masalah. IPA menekankan pentingnya pemantapan-diri sebelum ke lapangan dengan mematangkan panduan wawancara (interview schedule/interview guide) dan pembentukan rapport yang baik. Waktu wawancara juga diharapkan berjalan antara 45 me-nit sampai 90 menit. Banyak laporan penelitian yang menunjukkan bahwa wawancara yang hasilnya layak untuk dianalisis berlangsung dalam rentang waktu itu. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengutip langsung saja pandangan Jonathan A. Smith dkk. (2009:52) tentang frekuensi wawancara ini.
Teks Asli
Most studies have adopted straight-forward designs: recruiting small, homogenous groups of participants, and collecting data from them once. It is possible to be more adventurous, but of course, this does not make more demands on the analyst. Obviously, one option is to interview participants more than once. Certain longitudinal and “before-and-after” phenomena can benefit from this treatment (e.g. Smith, 1994.a, 1999a). There is also the possibility of using a first interview as a prompt for further discussion with a participant at a subsequent interview (e.g. see Smith, 1994b). Flowers (2008) considers some of the issues which arise with multiple interviews with the same participant.
Transkreasi
Banyak penelitian (IPA) menggunakan rancangan penelitian yang mudah diikuti: merekrut kelompok patisipan yang kecil dan homogen, dan mengum pulkan data dari mereka cukup sekali. Masih ada kemungkinan bagi peneliti untuk lebih bepertualang (misalnya, memperbesar jumlah partisipan dan mewawancarai satu partisipan lebih dari sekali) dengan risiko bahwa peneliti akan mendapatkan lebih banyak tuntutan dalam menjalankan analisis. Tentu saja, mewawancarai partisipan lebih dari sekali bisa dijadikan satu opsi. Wawancara lebih dari sekali bisa dirasakan manfaatnya dalam penelitian IPA yang longitudinal atau jangka panjang (misalnya, pengalaman ibu menjalani masa kehamilan dari waktu
BAB VI Persiapan ke Lapangan:Menjelang Wawancara 101
ke waktu sampai persalinan) dan ingin melihat pengalaman “sebelum dan sesudah” suatu peristiwa (misalnya, penga laman ibu sebelum dan sesudah persalinan). Ada juga kemungkinan bagi peneliti untuk menjadikan wawancara pertamanya sebagai tahap pendahuluan yang nantinya akan diperdalam lagi di pertemuan selanjutnya. Bagi yang ingin tahu lebih jauh masalah-masalah yang muncul terkait dengan wawancara yang dilakukan beberapa kali untuk satu partisipan, silakan membaca tulisan Flowers (2008) (yang berjudul Temporal Tales: The Use of Multiple Interviews with the Same Participant [Kisah-kisah Temporal: Penggunaan Wawancara Jamak dengan Partisipan yang Sama])
Demikianlah, keberhasilan wawancara ditentukan oleh tiga poin berikut: (1) panduan wawancara yang memenuhi syarat (kita sudah membicarakan ini di bab 5), (2) rapport (kepercayaan yang terbentuk) yang terlihat dari suasana yang nyaman dan cair selama wawancara berlangsung, dan (3) kedalaman penggalian informasi selama wawancara berlangsung. Segera setelah melakukan wawancara, dengarkan ulang seluruh wawancara dan transkripsikan. Bila ketiga poin tadi sudah terpenuhi dalam sekali pertemuan, maka wawancara satu kali sudah cukup.
103
BAB VII
Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): Analisis Data
Dalam Bab III, kita sudah berkenalan sekilas dengan interpretative pheno menological analysis (IPA). Dalam bab ini, kita akan memperdalam lagi pemahaman kita dengan membicarakan alur analisis data dalam IPA. Analisis data bisa dijalankan segera sesudah peneliti selesai mentranskripsikan rekaman wawancara dan memastikan bahwa datanya memuaskan dan layak dianalisis. Layak tidaknya data (transkrip) untuk dianalisis diketahui setelah kita membaca seluruh transkrip. Karena itu, peneliti sangat disarankan untuk segera mentranskripsikan hasil rekaman, membaca keseluruhan hasil transkrip, dan segera membuat keputusan apakah wawancara sudah cukup atau perlu ditindaklanjuti. Wawancara boleh saja dilakukan sekali sejauh empat syarat berikut terpenuhi.
1. Peneliti menyiapkan panduan wawancara yang mencermin kan epochē.
2. Peneliti membangun rapport (kepercayaan) yang baik dengan partisipan.
3. Peneliti mendengarkan dengan penuh perhatian selama wawancara. 4. Peneliti sudah merasa jelas saat membaca ulang seluruh transkrip
sehingga tidak lagi perlu diperjelas oleh partisipan.
Peneliti tidak perlu memaksakan diri untuk segera menganalisis data bila masih ada bagian transkrip yang butuh kejelasan. Transkrip yang
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup104
belum jelas akan mengganggu jalannya proses analisis. Umumnya, peneliti pada level S1 adalah peneliti pemula yang butuh dipandu, dikuatkan, dan diyakinkan bahwa mereka sudah menjalankan proses penelitian sesuai yang diharapkan. Dalam pengamatan saya, mahasiswa S1 sebagai peneliti pemula perlu dilihat sebagai mahasiswa yang belajar menggunakan metode. Mereka baru saja diperkenalkan dengan penelitian fenomenologis dan belajar menggunakannya. Mereka belum bisa disebut sebagai pengguna metode dalam pengertian ketat. Bila ada kekeliruan, pembimbing tentu saja dibutuhkan kehadirannya sebagai pembimbing atau pemandu atau penuntun.
Kembali ke kelayakan data untuk dianalisis. Ada seorang mahasiswi yang begitu bersemangat mengumpulkan data. Fenomena yang menjadi judul penelitiannya adalah pengalaman penderita bipolar. Setelah menjalankan wawancara, dia segera mentranskripsikan hasil rekaman. Saat ingin menganalisis transkrip wawancaranya, dia merasa ada istilah yang belum jelas dalam jawaban partisipan. Berikut potongan transkripnya.
P: PenelitiS: Subjek
P : Tadi kamu mengatakan mood swing, maksudnya?
S : Oo, yang mood swingnya … Emmm, pernah sampe marah-marah di grup line angkatan, pernah sampe, bahkan pernah sampe, ee, istilah, istilahnya ngelabrak cewek yang ganggu hubunganku sama pacarku. Itu sih tindakan-tindakan negatifnya trus sampe, emm, self injury gitu. Trus habis itu sampe apa ya, yang gak karuan banget itu. Bolos kuliah, sering bolos kuliah, nge-drop praktikum, sering nge-drop, e sering gak bisa ikut ujian karena kehadirannya kurang, sering dapet nilai D, E, sering nangis, jerit, ee, intinya apa ya, hancur bangetlah pokoknya rasanya tu, kayak sendirian kayak gak punya temen.
Istilah self-injury yang digarisbawahi dianggap oleh peneliti masih belum jelas. Idealnya, ketidakjelasan itu langsung diperjelas dengan bertanya lebih jauh saat wawancara. Karena mahasiswi itu tidak melakukannya, dia lalu kembali menemui partisipan dan bertanya lebih jauh tentang pengalaman self-injury itu. Berikut ini adalah informasi tambahan yang ia dapatkan.
BAB VII Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): Analisis Data 105
P : Oh iya, dalam pertemuan kita sebelumnya, kamu sempat cerita tentang self injury. Bisa diceritain apa yang kamu maksud dengan self-injury?
S : Nyilet-yilet tangan, gitu. Tapi kalo apa sih, itu karena ya perasaan itu malu, trus dibilang, waktu itu pernah dibilang, sama guru SD kalo aku tu anaknya susah berbaur gitu kan, bilang gitu trus aku denger. Nah aku kan jadinya kayak merasa ada dis, diskriminasi gitu lo, macem-macemlah masalah waktu SD.
Wawancara yang kedua memperjelas peristiwa “self-injury” yang belum jelas dalam wawancara pertama. Hasil wawancara (transkrip) adalah fondasi kita dalam menjalankan analisis data. Analisis data akan berjalan lancar bila data yang didapatkan layak dianalisis. Cukup sering terjadi bahwa data kurang layak dianalisis karena tiga hal berikut.
1. Persiapan wawancara yang belum matang
Sering kali data yang didapatkan kurang layak dianalisis karena persiapan yang kurang matang. Peneliti belum membatinkan pan-duan wawancara dan belum santai saat menjalankan wawancara. Jika panduan wawancara sudah dipersiapkan dengan baik, tetapi suasana belum relaks, maka wawancara sebaiknya ditunda dahulu sampai suasana menjadi relaks.
2. Tergesa-gesa selama wawancara
Peneliti diharapkan bisa melepaskan keinginan untuk segera men-dapatkan data, termasuk keinginan untuk bisa menganalisis sece-patnya. Peneliti fenomenologis diharapkan menjadi active listener (pendengar yang aktif ). Pendengar yang aktif itu sering kali lupa waktu. Ketika peneliti sedang mendengarkan partisipan yang ber-cerita, maka peneliti sebaiknya masuk ke dalam aliran cerita itu. Ajukan pertanyaan dengan pelan-pelan saja sehingga partisipan merasa diberi kesempatan bercerita. Bila partisipan terdiam di tengah cerita, peneliti tidak perlu terburu-buru menyela. Bisa saja, partisipan sedang membutuhkan waktu untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan atau pikirkan.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup106
3. Distorsi selama wawancara
Kadang-kadang terjadi bahwa peneliti sudah merasa mantap de-ngan persiapannya, tetapi situasi lapangan tidak memungkinkan untuk menerima data yang memuaskan karena adanya distorsi saat wawan cara. Seorang mahasiswi pernah bercerita tentang kesu-litan nya mengalir dalam wawancara karena mendapat gangguan dari anak partisipan yang masih kecil saat wawancara sedang ber-langsung. Ada juga yang bercerita tentang suami partisipan yang ingin ikut mendengarkan dan di luar kendali, sang suami ikut mem bantu menjawab. Situasi seperti itu memang berada di luar perencanaan. Solusinya adalah merancang pertemuan ulang atau, jika tidak memungkinkan, peneliti boleh menggugurkan partisipan dan mencari partisipan lain.
Saya sengaja memunculkan poin-poin tersebut untuk mengantisipasi situasi lapangan yang potensial menganggu aliran informasi atau data. Anggap saja sekarang Anda sudah mendapatkan data atau informasi dari partisipan yang layak untuk dianalisis. Informasi itu adalah informasi dari partisipan tentang pengalamannya yang ingin diteliti. Informasi itu pada awalnya berupa ucapan langsung yang direkam. Rekaman lisan itu kemudian diubah menjadi bentuk tertulis. Proses perubahan dari lisan menjadi ter-tulis disebut transkripsi. Hasil dari transkripsi itu disebut transkrip. Nah, transkrip inilah adalah dasar kita dalam menjalankan analisis. Skema berikut menunjukkan proses mendapatkan data berupa transkrip.
Perlu dilengkapi?
Wawancara Pasca-wawancara
ucapan langsung perekaman transkripsi transkrip
Transkrip adalah data mentah yang akan kita olah. Karena itu, penting sekali bagi peneliti untuk yakin bahwa data yang ia miliki sudah siap atau
BAB VII Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): Analisis Data 107
layak dianalisis. Kalau data yang didapatkan belum memuaskan, peneliti disarankan kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data. Karena itu, ada baiknya mengakhiri setiap wawancara dengan permohonan wawancara lanjut bila ada kekurangan data. Berikut pernyataan dan per tanyaan yang bisa digunakan.
1. Terima kasih untuk waktu yang disediakan. Seandainya saya perlu tambahan informasi, apakah saya boleh datang lagi?
2. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk wawancara ini. Seandainya masih ada yang perlu saya tanyakan, apakah saya boleh datang lagi?
Dalam pengalaman saya bertemu partisipan, tanggapan yang biasa saya terima: "Monggo. Boleh. Silakan. With pleasure. Any time."
Silakan kreatif merumuskan kalimat menurut selera kesantunan Anda dalam berbahasa. Intinya, kita meminta kesediaan partisipan untuk mem-buka diri bila kita datang lagi menemuinya untuk wawancara. Kita lebih baik datang lagi untuk melengkapi kekurangan wawancara daripada harus menganalisis informasi yang minim. Bila informasi minim, maka hasil analisisnya pun minim.
A. Epochē yang Dinamis
Bila data dirasakan sudah memuaskan, kita bisa menjalankan analisis atau pengolahan data. Dalam interpretative phenomenological analysis (IPA), proses pengolahan data mentah itu melewati proses interpretatif. Artinya, data mentah/transkrip akan diinterpretasikan langsung oleh peneliti. Dengan kata lain, sekarang saatnya peneliti menjalankan perannya sebagai sang penafsir untuk ucapan klien. Proses penafsiran itu melewati tahapan-tahapan. Analisis dalam IPA adalah proses penafsiran terhadap pengalaman pribadi dengan menjalankan epochē.
Saat menjalankan epochē, kita tidak harus benar-benar “sudah” bersih atau benar-benar “sudah” lepas dari pengaruh asumsi/dugaan/anggapan/penilaian/teori. Tidak harus seperti itu. IPA menjalankan epochē secara lebih lunak. IPA memandang bahwa proses pembersihan-diri bukan perkara gampang. IPA melihat epochē sebagai proses, sebagai dinamika. Karena itu,
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup108
peneliti IPA bertekad untuk “berproses menjadi bersih” dalam setiap proses interpretasi yang kita jalankan. Singkat kata, netralisasi diri (pembersihan diri) berjalan mengiringi proses interpretasi.
Epochē dalam IPA bukanlah suatu aktivitas yang dipisahkan dari data. Jika peneliti berjumpa dengan data dan dia berada dalam keadaan fokus dan penuh perhatian pada data, maka peneliti bisa dikatakan berada dalam keadaan epochē. Dalam bahasa Jawa, epochē itu adalah bersikap awas (penuh perhatian) saat membaca transkrip. Semakin awas peneliti saat membaca, semakin menyatu dia dengan transkrip. Semakin menyatu peneliti dengan transkrip, semakin besar peluang bagi peneliti untuk menarik keluar makna dari dalam transkrip itu.
B. Penyajian Transkrip Wawancara
Mari kita kembali ke transkrip yang merupakan bahan dasar analisis/proses interpretasi kita. Transkrip yang dianalisis akan disajikan dalam tampilan yang memudahkan kita untuk menjalankan analisis. Penyajian trans krip umumnya diawali dengan informasi tentang nama partisipan, tempat wawancara, tanggal wawancara, dan durasi wawancara. Berikut ini adalah contoh penyajian transkrip yang saya adaptasi dan kontekstualisasikan dari buku Jonathan A. Smith, dkk (2009) dan menjadi rujukan utama IPA.
Transkrip Wawancara Partisipan 1
Nama (Pseudonim) : Mira
Tanggal wawancara : 12-5-2017
Durasi wawancara : 55 menit
P: Peneliti
S: Subjek
P Bisa ceritakan lebih jauh tentang itu?
S Lebih jauh tentang itu eh … gak tahu gimana yah eh … menurutku sih itu terjadi karena aku, aku, aku gimana yah, saya gak ngerti aja kenapa aku bisa begitu waktu itu, saat aku terima diagnosis HIV. Aku gak bisa aja berhenti memikirkan hasil diagnosis dan eh … saya harus melewati
23242526
BAB VII Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): Analisis Data 109
masa itu dan eh rasanya seperti harus belajar lagi mengenal diriku sendiri. Orang-orang yang kenal aku tahu kondisiku. Aku capek banget… banget … dengan pikiranku sendiri. Aku mengkhawatirkan pikiran mereka tentang aku. Mereka Pasti tahu ada yang salah sama aku. Aku paranoid. Mereka bakal tahu tentang kondisiku. Aku berusaha menutupi dan berusaha tampil seperti orang yang gak hidup dengan HIV … tapi gak mungkin karena semakin kamu berusaha berhenti mikirin, semakin sering pikiran itu mengganggu.. Yah.. seperti itulah
272829303132333435
P Bisa ceritakan siapa “mereka” yang Anda maksud? Hmm.. apakah teman dekat?
S Teman dekat, keluarga, sahabat, siapa saja, bahkan orang yang baru aku temui. Aku hanya merasa gak bisa, aku aku gak bisa merasa gak berdaya karena aku gak lagi (mendesah) aku merasa kehilangan sesuatu yang aku gak bisa, aku em… aku udah capek, aku gak bisa, gak ada lagi yang bisa aku berikan, aku merasa aku gak pantas untuk berbagi … Gimana yah? Aku benar-benar shocked, seperti gempa … aku gak tahu apakah aku udah menjawab pertanyaanmu.
36373839404142
P Kamu tadi bilang ada perasaan kehilangan, [iya, iya] tidak punya arti [iya]. Bisa ceritakan apa yang terasa hilang?
Untuk apa penomoran itu? Apa gunanya? Itu hanya nomor, bukan angka. Nomor itu hanya digunakan sebagai alat bantu untuk menunjukkan baris ke berapa dalam keseluruhan transkrip. Tidak ada makna statistis dari penomoran itu. Perhatikan juga bahwa penomoran hanya diberikan pada ucapan partisipan. Pertanyaan peneliti tidak perlu diberi nomor karena fokus analisis terarah pada ucapan partisipan. Transkrip di atas bukan transkrip utuh, tetapi potongan transkrip yang menampilkan pernyataan partisipan pada baris 23-42.
Penomoran dilakukan paling akhir saja setelah kita yakin bahwa tidak ada lagi kesalahan pengetikan dalam transkrip. Perubahan ketikan pada transkrip bisa menggeser penomoran. Setelah yakin semua ketikan benar, beri nomor, dan kunci file transkrip agar tidak lagi ada pergeseran format. Transkrip yang sudah diberi nomor akan menjadi lampiran penelitian. Berikut kita perjelas lagi prosesnya.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup110
Perlu wawancara lanjut?
Wawancara Pasca-wawancara Pra-analisis
ucapan langsung perekaman
transkripsi transkrip periksa transkrip sampai yakin bebas dari kesalahan ketik penomoran ucap-an partisipan kunci/gembok file transkrip.
C. Analisis Transkrip
Urusan wawancara, transkripsi, dan transkrip kita anggap sudah benar-benar beres. Sebelum menjalankan analisis, saya ingin mengulangi dulu apa artinya analisis dalam IPA. Analisis dalam IPA adalah analisis terhadap transkrip dengan menjalankan tiga pilar penelitian dengan IPA, yaitu (1) fenomenologi yang bersandar pada epochē, (2) interpretasi yang bersandar pada pemahaman setiap pernyataan partisipan tanpa melepaskannya dari seluruh transkrip, dan (3) idiografi yang memperhatikan keunikan partisipan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menjalankan analisis data.
1. Membaca berkali-kali
Kalau saya dan Anda tidak sering bertemu, kita tidak bisa menjadi akrab. Kalau kita tidak sering membaca transkrip, kita tidak bisa menjadi akrab dengan transkrip. Tujuan dari membaca transkrip berkali-kali adalah menjadi akrab atau “menyatu” dengan transkrip. Transkrip itu sebenarnya adalah pengalaman partisipan dalam bentuk tertulis. Membaca transkrip berkali-kali menunjukkan upaya serius dari peneliti untuk menyatu dengan pengalaman partisipan. Dalam bahasa Indonesia, istilah “meng-hayat-i transkrip” sepertinya lebih cocok. Tidak perlu terburu-buru menganalisis. Biarkan “kesadaran” partisipan dalam transkrip itu menjadi akrab dengan “kesadaran” peneliti. Saya kadang-kadang bercanda kepada mahasiswa dengan
BAB VII Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): Analisis Data 111
mengatakan, “Setelah membuat transkrip, bakar transkrip itu. Abunya lalu dicampur dengan kopi dan minum biar menyatu dengan dirimu. ”
2. Membuat catatan-catatan awal (initial noting)
Setelah membaca berkali-kali dan menjadi akrab dengan transkrip, kita lalu membuat catatan-catatan awal. Sebagai peneliti, kita bisa membuat catatan-catatan awal dengan memberi komentar-komentar tentang maksud dari transkrip itu. Komentar peneliti disebut komentar eksploratoris (exploratory comment). Ekplorasi berarti menggali lebih dalam supaya paham. Sebelum berkomentar, soroti dulu bagian dari transkrip yang dirasakan penting disoroti. Pusatkan perhatian pada transkrip, rasakan transkrip, dan beri tanda untuk bagian yang penting dalam pernyatan partisipan. Sesudah itu, beri komentar terhadap bagian yang diangggap penting itu. Jadi, komentar di sini adalah pernyataan interpretatif peneliti terhadap pernyataan partisipan yang dirasakan penting dalam transkrip.
3. Membuat tema emergen
Setelah membuat komentar eksploratoris, kita sekarang mau membuat tema emergen. Kita tidak lagi membuat komentar, tetapi membuat tema. Tema yang kita buat pada dasarnya adalah pemadatan dari komentar yang kita buat sebelumnya. Tema tidak lagi berupa pernyataan, tetapi berupa kata atau frasa (kelompok kata).
4. Membuat tema superordinat
Tema emergen yang ditemui umumnya berjumlah banyak. Ada saatnya beberapa tema emergen ditampung dalam satu tema yang lebih besar. Kita menyebut tema yang lebih besar itu sebagai tema superordinat. Saya sering menganalogikan tema superordinat itu dengan folder yang berisi beberapa file yang dianggap memiliki kemiripan ciri. Kita, misalnya, memiliki 150 file lagu dan ingin mengelompokkannya berdasarkan kemiripan “genre” musik. Kita lalu membuat beberapa folder yang menampung 150 file lagu itu. Bisa saja 150 file itu dikelompokkan menjadi beberapa folder: folder dangdut pantura, folder jazz, folder instrumental, folder rock, folder …., teruskan sendiri menurut klasifikasi yang Anda rasa sesuai. Saya
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup112
hanya mau mengatakan bahwa tema superordinat adalah tema yang menampung beberapa tema emergen yang memiliki kemiripan makna.
Empat langkah tersebut bertujuan menarik keluar tema-tema dari dalam transkrip tiap-tiap partisipan. Mula-mula kita memiliki transkrip, lalu tema emergen, lalu tema superordinat. Komentar eksploratoris pasti terhubung dengan transkrip. Tema emergen pasti terhubung dengan komentar eksplora-toris. Tema superordinat pasti terhubung dengan tema-tema emergen. Semuanya saling terkait, seperti yang ditunjukkan skema berikut.
transkrip komentar eksploratoris tema emergen tema superordinat
Tahap Analisis 1 dan 2: Penghayatan Transkrip dan Pencatatan Awal
Mari kita perjelas langkah-langkah tersebut dengan contoh. Mari kita kembali ke potongan transkrip tersebut, membacanya, menghayatinya, dan mulai menginterpretasikannya. Prosesnya begini.
1. Baca transkrip dan hayati isinya secara menyeluruh.
2. Buat tabel dengan tiga kolom: (1) kolom paling kiri adalah transkrip orisinal, (2) kolom tengah adalah catatan-catatan awal berupa komentar eksplora toris, (3) kolom paling kanan adalah tema emergen.
3. Masukkan seluruh transkrip pada kolom paling kiri dan peneliti kembali menghayati transkrip itu. Peneliti kemudian memeriksa transkrip secara detail dan memberi komentar untuk bagian-bagian yang dianggap bermakna. Komentar diberikan dari awal sampai akhir transkrip.
Perhatikan informasi dalam Kotak 7.1. Kolom satu dan kolom dua adalah kerepotan kita untuk saat ini. Perhatikan bagaimana komentar eksploratoris terhubung dengan transkrip orisinal. Kolom tiga kita abaikan dulu. Ada saatnya nanti di Bab 8 kita membicarakannya secara khusus.
BAB VII Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): Analisis Data 113
Kot
ak 7
.1 T
rans
krip
Oris
inal
dan
Pen
cata
tan
Awa
l
Tran
skrip
oris
inal
Kom
enta
r eks
plor
ator
isTe
ma e
mer
gen
Apak
ah A
nda b
isa ce
ritak
an le
bih
jauh
ten
tang
itu?
Lebi
h jau
h te
ntan
g itu
eh …
gak
tahu
gi
man
a yah
eh …
men
urut
ku si
h itu
te
rjadi
kar
ena a
ku, a
ku, a
ku g
iman
a ya
h, ak
u ga
k ng
erti
aja k
enap
a aku
bi
sa k
ayak
gitu
wak
tu ak
u te
rima
diag
nosis
HIV
. Aku
gak
bisa
aja
berh
enti
mem
ikirk
an h
asil
diag
nosis
da
n em
… sa
ya h
arus
mele
wati
mas
a itu
dan
em r
asan
ya se
perti
har
us
belaj
ar la
gi m
enge
nal d
iriku
send
iri.
Ora
ng-o
rang
yan
g ke
nal a
ku ta
hu
kond
isiku
. Aku
cape
k ba
nget
…
bang
et …
den
gan
piki
rank
u se
ndiri
. A
ku m
engk
hawa
tirka
n pi
kira
n m
erek
a ten
tang
aku.
Men
gula
ng “e
h” “a
ku” d
an “g
ak ta
hu gi
man
a yah
?” A
paka
h ad
a kes
ulita
n m
engu
ngka
pkan
per
asaa
n? A
da h
amba
tan
dalam
men
gung
kapk
an
pera
saan
yan
g su
lit. H
amba
tan
itu je
las d
alam
peng
ulan
gan
“aku
” dan
“gak
ta
hu gi
man
a yah
”.
Ada
per
tany
aan
yang
dia
juka
n ke
diri
send
iri. M
eras
a tid
ak ta
hu k
ondi
si di
ri se
ndiri
pad
a wak
tu it
u. K
enap
a dia
bisa
beg
itu w
aktu
itu?
Ini d
ampa
k da
ri di
agno
sis.
Melu
lu m
emik
irkan
has
il di
agno
sis H
IV.
Men
galam
i mas
a krit
is. A
paka
h in
i mas
a yan
g sa
ngat
sens
itif d
alam
hi
dupn
ya? B
elajar
men
gena
l diri
? Gak
lagi
men
gena
l diri
? d
ampa
k di
agno
sis.
Apa
artin
ya o
rang
lain
? Apa
kah
ini d
ampa
k so
sial h
asil
diag
nosis
?M
eras
a let
ih. P
engu
lang
an “b
ange
t” ses
udah
“cap
ek” m
enek
anka
n ke
rja ke
ras
mem
ikirk
an so
lusi.
M
enga
ntisi
pasi
peni
laian
ora
ng la
in se
suda
h di
agno
sis. D
ampa
k di
agno
sis.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup114
Mer
eka p
asti
tahu
ada y
ang
salah
sa
ma a
ku. A
ku p
aran
oid.
Mer
eka
baka
l tah
u te
ntan
g ko
ndisi
ku. A
ku
beru
saha
men
utup
i dan
ber
usah
a ta
mpi
l sep
erti
oran
g ya
ng g
ak h
idup
de
ngan
HIV
… ta
pi g
ak m
ungk
in
kare
na se
mak
in k
amu
beru
saha
be
rhen
ti m
ikiri
n, se
mak
in se
ring
piki
ran
itu m
engg
angg
u.. Y
ah..
sepe
rti
itulah
Apa
kah
“salah
” ber
arti
dulu
nya b
aik
seka
rang
suda
h ga
k ba
ik? I
ni te
ntan
g pe
nam
pilan
di d
epan
ora
ng. A
paka
h “p
aran
oid”
ber
arti
taku
t aka
n kh
awat
ir or
ang
lain?
Kok
has
il m
edis
bisa
mem
beri
dam
pak
sepa
rah
ini?
Upa
ya y
ang
dian
ggap
mus
tahi
l.G
ejolak
pik
iran
dalam
diri
send
iri. A
paka
h un
gkap
an in
i men
unju
kkan
pe
rasa
an d
ipen
jara o
leh p
ikira
n se
ndiri
? Ini
dam
pak
dari
diag
nosis
.
Bisa
cerit
akan
siap
a “m
erek
a” ya
ng
Anda
mak
sud?
Hm
m..
apak
ah te
man
de
kat?
Tem
an d
ekat
, kelu
arga
, sah
abat
, sia
pa
saja,
bah
kan
oran
g ya
ng b
aru
aku
tem
ui. A
ku h
anya
mer
asa g
ak b
isa,
aku
aku
gak
bisa
mer
asa g
ak b
erda
ya
kare
na ak
u ga
k lag
i (m
ende
sah)
aku
mer
asa k
ehila
ngan
sesu
atu
yang
aku
gak
bisa
, aku
em…
aku
udah
cape
k,
Kha
watir
dala
m p
erju
mpa
an d
enga
n sia
pa sa
ja ya
ng d
item
ui. M
ulai
dar
i or
ang
yang
ken
al de
kat s
ampa
i ora
ng y
ang
kena
l sam
bil l
alu.
Ada
rasa
tida
k be
rday
a. Pe
ngul
anga
n ka
ta “a
ku” d
an “g
ak bi
sa” m
empe
rkua
t ra
sa ti
dak b
erda
ya it
u.
Men
desa
h (ra
sa se
dih?
). D
ia m
eras
a keh
ilang
an.
Dia
mer
asa s
egala
nya s
udah
mele
lahka
n.
BAB VII Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): Analisis Data 115
aku
gak
bisa
, gak
ada l
agi y
ang
bisa
ak
u be
rikan
, aku
mer
asa a
ku g
ak
pant
as u
ntuk
ber
bagi
… G
iman
a ya
h? A
ku b
enar
-ben
ar sh
ocked
, sep
erti
gem
pa …
aku
gak
tahu
apak
ah ak
u ud
ah m
enjaw
ab p
erta
nyaa
nmu.
Tid
ak ad
a lag
i yan
g di
rasa
ber
arti
pada
diri
send
iri. A
da y
ang
agak
jan
ggal
dalam
uca
pan
di si
ni. D
ia m
eras
a tid
ak b
isa b
erba
gi. A
paka
h di
a du
luny
a ora
ng y
ang
sena
ng b
erba
gi?
“shock
ed”,
“sepe
rti ge
mpa
” men
unju
kkan
gunc
anga
n pe
rasa
an ya
ng lu
ar bi
asa.
Ini d
ampa
k dia
gnos
is.
Kam
u ta
di b
ilang
ada p
eras
aan
kehi
langa
n, [i
ya, i
ya] t
idak
pun
ya ar
ti [iy
a]. B
isa ce
ritak
an ap
a yan
g te
rasa
hi
lang?
Saya
han
ya m
enge
cek
ulan
g. D
ia m
enan
gis.
Suas
ana y
ang
sang
at
emos
iona
l.
Kom
enta
r: Pe
rhat
ikan
bah
wa b
ahas
a yan
g di
guna
kan
dalam
kom
enta
r eks
plor
ator
is tid
ak le
pas d
ari k
alim
at, b
ahka
n ba
gian
dar
i ka
limat
juga
dia
nalis
is, te
rmas
uk m
ajor
pro
sodic
featu
re (c
iri-c
iri y
ang
men
yerta
i uca
pan)
, sep
erti
ters
enyu
m, m
ende
sah,
dan
lain
-lain
. Pe
mer
iksa
an it
u di
lakuk
an se
cara
det
ail.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup116
Saat membaca transkrip, jalankan epochē. Saat Anda fokus, tenang, dan penuh perhatian, Anda sebenarnya menjalankan epochē. Dalam keadaan epochē itu, komentari transkrip secara spontan, mengalir, dan penuh perhatian.
Perhatikan juga macam-macam bentuk tulisan pada kolom kedua di atas: (1) ada ketikan biasa, (2) ada ketikan miring, dan (3) ada ketikan dengan garis bawah. Begini penjelasannya.
• Ketikan biasa berarti komentar deskriptif (descriptive comment). Komentar deskriptif adalah komentar yang menggambarkan/mendeskripsikan isi ucapan/omongan partisipan kita. Yang kita soroti adalah isi dari ucapan.
• Ketikan miring berarti komentar linguistis (linguistic comment). Komentar linguistis adalah komentar untuk penggunaan bahasa oleh partisipan kita. Yang kita soroti adalah penggunaan bahasa.
• Ketikan dengan garis bawah berarti komentar konseptual (conceptual comment). Komentar konseptual berarti komentar yang menunjukkan pertanyaan kritis yang bergejolak dalam pikiran peneliti saat membaca transkrip.
Jadi, ada tiga jenis komentar eskploratoris, yaitu (1) komentar deskriptif, (2) komentar linguistis, dan (3) komentar konseptual. Saat membuat komentar eksploratoris, peneliti sebaiknya membuat tulisan tangan. Penyajian yang rapi boleh dilakukan kemudian. Tulisan tangan lebih spontan dan mengalir. Dalam ujian skripsi atau tesis, peneliti boleh memperlihatkan analisis yang masih dalam bentuk tulisan tangan itu sebagai bukti keseriusan menganalisis.
Baiklah, pembicaraan kita dalam bab ini dicukupkan sampai pada komentar eksploratoris. Kalau Anda sudah punya transkrip, lakukan dulu dua tahap yang baru saja kita bicarakan: (1) membaca transkrip seluruhnya sampai akrab dan (2) membuat komentar eksploratoris sampai tuntas. Masih ada tiga tahap analisis yang tersisa. Kita akan menuntaskan tahap analisis ini di bab selanjutnya.
117
BAB VIII
Interpretative Phenomenologial Analisis (IPA): Analisis Data Lanjutan
Ada seorang mahasiswa yang menarik perhatian saya karena begitu ber-semangat melakukan riset kualitatif, khususnya IPA. Dia datang menemui saya dan bercerita bahwa dia sudah selesai mewawancarai satu subjek atau partisipannya dan tanpa menunda dia juga sudah mentranskripsikan hasil wawancara itu. Ini contoh yang bagus untuk ditiru. Peneliti sebaiknya meng-hindari penundaan transkripsi agar informasi yang kurang dan tidak jelas bisa dideteksi dan dilengkapi dengan cepat. Nah, mahasiswa tadi sudah mencoba membuat komentar eksploratoris. Dia juga sudah mulai memikirkan membuat tema-tema emergen. Dalam obrolan kami, terungkap bahwa dia belum tuntas dengan komentar eksploratoris, tetapi sudah memikirkan tema emergen. Saya memintanya menuntaskan dahulu komentar eksploratoris dan mengabaikan tema emergen dan tema superordinat.
Semangat peneliti seperti itu adalah energi untuk melancarkan penelitian sampai tuntas. Meski demikian, peneliti perlu juga berlatih menahan diri untuk tidak tergesa-gesa meloncat ke perumusan tema sebelum mantap dengan komentar eksploratoris. Arah analisis data dalam IPA bisa divisualisasikan, seperti yang ditunjukkan dalam Kotak 8.1.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup118
Kotak 8.1 Alur Analisis Data
Transkrip orisinal Komentar eksploratoris Tema emergen
Tuntaskan Tuntaskan Tuntaskan
Anggap saja Anda sudah selesai dengan komentar eksploratoris dan bersiap untuk menarik tema-tema emergen. Sebelum sampai ke tema emergen itu, kita review sedikit perjalanan analisis kita sejauh ini.
• Sebelumnyakitasudahmembicarakanproses(1)membacatranskripberulang kali dan kemudian (2) membuat komentar eksploratoris.
• Sekarang kita mau membicarakan (3) perumusan tema emergensatu partisipan dan kemudian (4) perumusan tema superordinat satu par tisipan, dan akhirnya (5) perumusan tema superordinat antar-partisipan.
A. Tahap Analisis 3: Perumusan Tema Emergen
Dengan selesainya komentar eksploratoris, kita kembali membaca tema eksploratoris itu dari awal sambil menarik keluar tema-tema emergen. Kata Inggris “emerge” berarti “keluar” atau “muncul”. Tema emergen atau tema yang keluar dari komentar eksploratoris bisa berupa kata atau frasa. Kata atau frasa itu adalah hasil dari permenungan peneliti terhadap komentar-komentar eksploratoris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kita mendapat penjelasan berikut untuk kata dan frasa.
kata/ka·ta/ n 1 unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa; 2 ujar; bicara; 3 Ling a morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas; b satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal (misalnya batu, rumah, datang) atau gabungan morfem (misalnya pejuang, pancasila, mahakuasa);-- berjawab, gayung bersambut, pb balas kecaman dengan cepat dan tepat; -- dahulu bertepati,
BAB VIII Interpretative Phenomenologial Analisis (IPA): Analisis Data Lanjutan 119
-- kemudian kata bercari, pbjanji harus ditepati dan hanya boleh diubah setelah diperoleh kebulatan kata pula;elok -- dalam mufakat, buruk -- di luar mufakat, pb apa yang hendak dikerjakan sebaiknya dibicarakan dulu dengan teman sejawat atau kaum keluarga, dan sebagainya;
frasa/fra·sa/ n Ling gabungan dua kata atau lebih yang bersifat nonpredikatif (misalnya gunung tinggi disebut frasa karena merupakan konstruksi nonpredikatif);
Bagian yang digarisbawahi adalah makna dari “kata” dan “frasa” yang saya maksudkan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh dan bertemu langsung dengan frasa atau kata itu. Saya munculkan lagi transkrip yang ada di bab sebelumnya. Kali ini, aktivitas kita adalah memperhatikan kolom transkrip dan komentar eksploratoris sambil mengisi tema emergen pada kolom paling kanan (lihat Kotak 8.2). Dalam buku Interpretative Phenomenological Analysis yang ditulis Jonathan A. Smith, dkk. (2009), kolom tema emergen tidak diposisikan di sebelah kanan, tetapi sebelah kiri. Kalau Anda kidal, kolom tema emergen sebaiknya diletakkan di sebelah kiri agar lebih nyaman saat menulis.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup120
Kot
ak 8
.2 P
enge
mba
ngan
Tem
a Em
erge
n
Tran
skrip
oris
inal
Kom
enta
r eks
plor
ator
isTe
ma e
mer
gen
Apak
ah A
nda b
isa ce
ritak
an le
bih
jauh
ten
tang
itu?
Lebi
h jau
h te
ntan
g itu
eh …
gak
ta
hu g
iman
a yah
eh …
men
urut
ku
sih it
u te
rjadi
kar
ena a
ku, a
ku, a
ku
gim
ana y
ah, s
aya g
ak n
gerti
aja
kena
pa ak
u bi
sa k
ayak
gitu
wak
tu
aku
terim
a dia
gnos
is H
IV. A
ku
gak
bisa
aja b
erhe
nti m
emik
irkan
ha
sil d
iagn
osis
dan
em …
saya
ha
rus m
elewa
ti m
asa i
tu d
an
em r
asan
ya se
perti
har
us b
elajar
lag
i men
gena
l diri
ku se
ndiri
. O
rang
-ora
ng y
ang
kena
l aku
tahu
ko
ndisi
ku. A
ku ca
pek
bang
et…
ba
nget
… d
enga
n pi
kira
nku
send
iri.
Aku
men
gkha
watir
kan
piki
ran
mer
eka t
enta
ng ak
u. M
erek
a Pas
ti ta
hu ad
a yan
g sa
lah sa
ma a
ku. A
ku
para
noid
. Mer
eka b
akal
tahu
tent
ang
kond
isiku
. Aku
ber
usah
a men
utup
i da
n be
rusa
ha ta
mpi
l sep
erti
oran
g ya
ng g
ak h
idup
den
gan
HIV
…
Men
gula
ng “e
h” “a
ku” d
an “g
ak ta
hu gi
man
a yah
?” A
paka
h ad
a ke
sulit
an m
engu
ngka
pkan
per
asaa
n? A
da h
amba
tan
dalam
m
engu
ngka
pkan
per
asaa
n ya
ng su
lit. H
amba
tan
itu je
las d
alam
pe
ngul
anga
n “a
ku” d
an “g
ak ta
hu gi
man
a yah
”. A
da p
erta
nyaa
n ya
ng d
iaju
kan
ke d
iri se
ndiri
. Mer
asa t
idak
tahu
ko
ndisi
diri
send
iri p
ada w
aktu
itu.
Ken
apa d
ia b
isa b
egitu
wak
tu
itu? I
ni d
ampa
k da
ri di
agno
sis.
Melu
lu m
emik
irkan
has
il di
agno
sis H
IV.
Men
galam
i mas
a krit
is. A
paka
h in
i mas
a yan
g sa
ngat
sens
itif
dalam
hid
upny
a? B
elajar
men
gena
l diri
? Gak
lagi
men
gena
l diri
?
dam
pak
diag
nosis
.A
pa ar
tinya
ora
ng la
in? A
paka
h in
i dam
pak
sosia
l has
il di
agno
sis?
Mer
asa l
etih
. Pen
gula
ngan
“ban
get”
sesud
ah “c
apek
” m
enun
jukk
an
kerja
kera
snya
mem
ikirk
an so
lusi.
M
enga
ntisi
pasi
peni
laian
ora
ng la
in se
suda
h di
agno
sis. D
ampa
k di
agno
sis.
Apa
kah
“salah
” ber
arti
dulu
nya b
aik
seka
rang
suda
h ga
k ba
ik? I
ni
tent
ang
pena
mpi
lan d
i dep
an o
rang
. Apa
kah
“par
anoi
d” b
erar
ti ta
kut a
tau
khaw
atir
oran
g lai
n? K
ok h
asil
med
is bi
sa m
embe
ri da
mpa
k se
para
h in
i?
Diri
yan
g m
em pe
r tany
a-ka
n di
ri se
ndiri
Ras
a tid
ak m
enen
tu
Piki
ran
yang
ber
ulan
g
Upa
ya m
enge
nal l
agi d
iri
send
iriR
elasi
sosia
l yan
g te
r-ga
nggu
Kele
tihan
Kek
hawa
tiran
akan
pe-
nilai
an o
rang
lain
Perh
atia
n pa
da p
enam
-pi
l an d
iriPe
nyem
buny
ian
kond
isi
diri
Piki
ran
yang
ber
ulan
g
BAB VIII Interpretative Phenomenologial Analisis (IPA): Analisis Data Lanjutan 121
tapi
gak
mun
gkin
kar
ena s
emak
in
kam
u be
rusa
ha b
erhe
nti m
ikiri
n,
sem
akin
serin
g pi
kira
n itu
m
engg
angg
u.. Y
ah..
sepe
rti it
ulah
Solu
si ya
ng d
iang
gap
mus
tahi
l dija
lanka
n.
Piki
ran
beru
lang
yang
sem
akin
kua
t. A
paka
h un
gkap
an in
i m
enun
jukk
an p
eras
aan
dipe
njar
a oleh
pik
iran
send
iri? I
ni d
ampa
k da
ri di
agno
sis.
Bisa
cerit
akan
siap
a “m
erek
a” ya
ng
Anda
mak
sud?
Hm
m..
apak
ah te
man
de
kat?
Tem
an d
ekat
, kelu
arga
, sah
abat
, sia
pa sa
ja, b
ahka
n or
ang
yang
bar
u ak
u te
mui
. Aku
han
ya m
eras
a ga
k bi
sa, a
ku ak
u ga
k bi
sa m
eras
a ga
k be
rday
a kar
ena a
ku g
ak la
gi
(men
desa
h) ak
u m
eras
a keh
ilang
an
sesu
atu
yang
aku
gak
bisa
, aku
em…
ak
u ud
ah ca
pek,
aku
gak
bisa
, gak
ad
a lag
i yan
g bi
sa ak
u be
rikan
, aku
m
eras
a aku
gak
pan
tas u
ntuk
ber
bagi
…
Gim
ana y
ah? A
ku b
enar
-ben
ar
shock
ed, s
eper
ti ge
mpa
… a
ku g
ak
tahu
apak
ah ak
u ud
ah m
enjaw
ab
perta
nyaa
nmu.
Kha
watir
dala
m p
erju
mpa
an d
enga
n sia
pa sa
ja ya
ng d
item
ui. M
ulai
da
ri or
ang
yang
ken
al de
kat s
ampa
i ora
ng y
ang
kena
l sam
bil l
alu.
Ada
rasa
tida
k be
rday
a. Pe
ngul
anga
n ka
ta “a
ku” d
an “g
ak bi
sa”
mem
perk
uat r
asa t
idak
berd
aya i
tu.
Men
desa
h (ra
sa se
dih?
). D
ia m
eras
a keh
ilang
an.
Dia
mer
asa s
egala
nya s
udah
mele
lahka
n.
Tid
ak ad
a lag
i yan
g di
rasa
ber
arti
pada
diri
send
iri. A
da y
ang
agak
jang
gal d
alam
uca
pan
di si
ni. D
ia m
eras
a tid
ak b
isa b
erba
gi.
Apa
kah
dia d
ulun
ya o
rang
yan
g se
nang
ber
bagi
? “sh
ocked
”, “se
perti
gem
pa” m
enun
jukk
an gu
ncan
gan
pera
saan
yang
luar
bi
asa.
Ini d
ampa
k dia
gnos
is.
Rela
si so
sial y
ang
terg
angg
uK
etid
akbe
rday
aan
Ras
a keh
ilang
an d
iri
Kele
tihan
Dep
resi?
Gun
cang
an em
osio
nal
Kam
u ta
di b
ilang
ada p
eras
aan
kehi
langa
n, [i
ya, i
ya] t
idak
pun
ya ar
ti [iy
a]. B
isa ce
ritak
an ap
a yan
g te
rasa
hi
lang?
Saya
han
ya m
enge
cek
ulan
g. D
ia m
enan
gis.
Mom
en y
ang
sang
at
emos
iona
l.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup122
Bila kolom paling kanan (tema emergen) tersebut diperhatikan lebih serius, maka akan terlihat berikut ini.
• Ada tema berupa kata. Misalnya: keletihan, ketidakberdayaan, depresi.• Ada tema berupa frasa. Tema berupa frasa paling sering ditemui.
Frasa bisa pendek (dua kata saja) dan bisa juga agak panjang (lebih dari dua kata). Itu bukan masalah asalkan benar-benar menunjukkan kesesuaian dengan komentar eksploratoris.
• Ada temaberupakatayangdiikuti tanda tanya. Tanda tanya seperti itu biasanya muncul ketika peneliti membuat tema emergen sambil bertanya dalam hati “Apakah bunyi tema ini sudah tepat?” Dengan kata lain, peneliti masih ragu dengan tema emergennya.
• Adatemayangmuncullebihdarisekali. Ini juga bukan masalah.
Siapa yang menentukan bunyi tema emergen? Peneliti adalah penentunya. Apakah ada pedoman baku untuk membuat tema emergen? Bunyi tema emergen tidak mungkin persis sama dari peneliti yang satu ke peneliti yang lain. Peneliti IPA harus menerima bahwa pilihan kata itu subjektif. Setiap peneliti punya perbendaharaan kata yang berbeda-beda dan selera bahasa mereka pun berbeda-beda. Yang penting untuk diingat, kita mengemukakan tema-tema emergen yang tidak melenceng dari ucapan partisipan. Kita menggunakan istilah-istilah yang sedekat mungkin dengan ucapan partisipan. Dalam Bab II, saya mengemukakan definisi fenomenologi dari Jonathan A. Smith dkk (2009) tentang pentingnya membicarakan pengalaman partisipan dengan melekat pada pengalaman itu sendiri. Mari kita segarkan lagi dan perhatikan bagian yang dicetak tebal:
Teks Asli
Phenomenology is a philosophical approach to the study of experience ... the founding principle of phenomenological inquiry is that experience should be examined in the way that it occurs, and in its own terms.
Transkreasi
Fenomenologi adalah pendekatan filo-sofis untuk penelitian tentang penga-laman … prinsip dasar dari pene liti an fenomenologis ada lah bahwa penga laman harus dite liti de ngan mem per hatikan bagai mana pengalaman itu ter jadi [da lam kehidupan seseorang] dan [dibicara kan] dalam istilah-istilah yang tidak dilepaskan dari pengalaman itu.
BAB VIII Interpretative Phenomenologial Analisis (IPA): Analisis Data Lanjutan 123
Dalam proses analisis, subjektivitas peneliti bertemu dengan subjektivitas partisipan. Proses ini menunjukkan bahwa peneliti fenomenologis harus mengakui bahwa dia subjektif dalam memahami subjektivitas partisipannya. Subjektivitas yang terhubung dengan subjektivitas disebut intersubjektivitas. Intersubjektivitas membentuk pemahaman yang objektif. Inilah yang di-harapkan terjadi dalam penelitian fenomenologis. Ini jugalah yang dimaksud Carl Gustav Jung dalam kutipan yang menjadi renungan di awal buku ini.
Dalam merumuskan tema emergen, kita bebas memilih kata atau frasa dalam keadaan epochē. Kata atau frasa yang digunakan dimunculkan dari komentar eksploratoris di mana komentar eksploratoris itu berakar pada transkrip.
B. Tahap Analisis 4: Perumusan Tema Superordinat
Sekarang, kita beranjak ke tema superordinat. Kata Inggris “superordinate” terdiri dari dua kata, yaitu “super” yang berarti “di atas” dan “ordinate” yang berarti “tatanan”. Tema superordinat berarti tema yang posisinya berada di atas tema-tema emergen. Tema superordinat menampung beberapa tema emergen. Dalam bab sebelumnya saya mengibaratkan tema superordinat dengan folder yang menampung beberapa file lagu yang genrenya mirip atau sejenis.
Membuat tema superordinat bisa dilakukan dalam macam-macam cara. Kalau Anda punya strategi sendiri yang Anda rasa bagus, silakan digunakan. Silakan berkreasi. Di sini, saya ingin menawarkan tiga cara.
1. Membuat garis berwarna
Copy semua tema emergen yang ada pada kolom paling kanan dan pindahkan ke halaman baru pada word yang masih kosong. Sebar dan cetak tema-tema itu dalam satu kertas. Letakkan di meja. Perhatikan dengan tenang sebaran tema-tema itu. Cukup dilihat dengan penuh perhatian dan biarkan pikiran pelan-pelan menangkap hubungannya satu sama lain. Dengan berfokus hanya pada tema, kita menjalankan epochē. Siapkan juga beberapa polpen atau pensil berwarna. Ambil polpen dengan warna tertentu dan buat garis yang menghubungkan satu tema dengan tema lain yang dirasa ada hubungannya. Tema-tema yang terhubung nantinya dikelompokkan tersendiri dan diberi
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup124
nama atau label yang mengikat semua tema itu. Silakan diutak-atik sampai merasa yakin dengan keterhubungan antartema itu. Keluarkan tema-tema yang warna garisnya sama dan kemudian beri satu nama untuk kumpulan tema itu. Nah, nama yang kita berikan untuk sekelompok tema emergen itu disebut tema superordinat.
2. Menyebar tema dalam potongan kertas
Tulis tema pada kertas yang berukuran kartu domino. Boleh juga lebih kecil daripada kartu domino. Di setiap potongan kertas, tulis satu tema emergen. Tema itu disebar di lantai atau diselotip di tembok kamar. Ambil jarak dari kertas-kertas tema itu. Lihat dari kejauhan sambil sesekali mendekat untuk menggeser satu kertas dan mendekatkannya dengan kertas lain yang dirasakan memiliki kemiripan. Ada saatnya nanti, tema-tema itu berkelompok. Silakan menggeser ke sana dan ke sini sampai merasa yakin dengan keter-hubungannya. Cara seperti ini digunakan oleh seorang teman saya saat menyusun tesisnya di Inggris. Saat saya datang mengunjunginya, saya melihat dinding rumah yang penuh dengan kertas tema emergen. Terkesan berantakan, tetapi menyenangkan untuk dilihat.
3. Menyebar tema di halaman word pada monitor komputer
Sebarkan tema di halaman kosong pada Word dan tema-tema yang dirasakan memiliki keterhubungannya di beri warna yang sama. Mari kita ambil tema-tema emergen pada contoh di atas. Beri warna yang sama untuk tema-tema yang dianggap memiliki kedekatan (lihat Kotak 8.3).
Kotak 8.3 Sebaran Awal Tema Emergen*
• diri yang mempertanyakan diri sendiri• rasa tidak menentu• pikiran yang berulang• upaya mengenal lagi diri sendiri • relasi sosial yang terganggu• keletihan • kekhawatiran akan penilaian orang lain• perhatian pada penampilan-diri
• penyembunyian kondisi diri• pikiran yang berulang• relasi sosial yang terganggu• ketidakberdayaan • rasa kehilangan • keletihan• depresi? • guncangan emosional
* Lihat Lampiran Kotak Berwarna
BAB VIII Interpretative Phenomenologial Analisis (IPA): Analisis Data Lanjutan 125
Komentar: Di sini kita bertemu dengan beberapa tema saja. Ini hanya contoh dari potongan transkrip. Jika seluruh transkrip dianalisis, kita akan bertemu dengan tema yang jumlahnya bisa mencapai ratusan. Ada saatnya tema yang berulang, tumpang tindih, dan tidak relevan dengan penelitian digugurkan sehingga yang tersisa hanya satu, seperti tema-tema yang dicoret di atas.
Jadi, ada tahap di mana kita memilih tema-tema yang relevan dengan pertanyaan penelitian kita. Bila kita belum begitu yakin dengan kata atau frasa tertentu, kita boleh menambahkan tanda tanya. Jika kita sudah yakin dengan pilihan kata atau frasa, maka tanda tanya boleh dihilangkan. Dalam Kotak 8.3, tema “depresi” semula meragukan sehingga diberi tanda tanya, tetapi bila kita kemudian merasa yakin dengan tema itu, tanda tanya boleh dihilangkan. Tema-tema yang sewarna kemudian dikelompokkan, seperti yang terlihat dalam Kotak 8.4.
Kotak 8.4 Pengelompokan Tema
• pikiranyangberulang• ketidakberdayaan• keletihan• depresi• guncanganemosional
• diriyangmempertanyakandirisendiri• upayamengenallagidirisendiri• perhatianpadapenampilan-diri• penyembunyiankondisidiri• diriyangtertutup
Komentar: Di sini kita bertemu dengan dua pengelompokan tema saja. Kita juga sudah yakin dengan tema depresi yang tadinya meragukan. Jika seluruh transkrip dianalisis, kita akan bertemu dengan beberapa kelompok tema.
Tema-tema yang sudah berkelompok itu, akan diberi nama apa? Bagai-mana kalau diberi nama “…” atau mungkin nama “….” Silakan berproses dan memantapkan pilihan istilah. Mari kita beranggapan saja bahwa kita sudah menemukan nama yang cocok. Untuk tema-tema dalam kolom yang berwarna abu-abu, kita sebut “Dampak psikologis dari HIV” dan untuk yang tema dalam kolom yang berwarna putih, kita sebut “Perubahan-
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup126
diri akibat diagnosis”. Nah, Kita sekarang sudah ketemu dengan dua tema superordinat.
Kotak 8.5 Pengembangan Tema Superordinat
Dampak psikologis dari HIV Perubahan-diri akibat diagnosis
• pikiranyangberulang• ketidakberdayaan• keletihan• depresi• guncanganemosional
• rasakehilangandiri• diriyangmempertanyakandiri
sendiri• perhatianpadapenampilan-diri• penyembunyiankondisidiri• diriyangtertutup
Tema-tema emergen dan tema-tema superordinat di atas hanyalah con-toh. Kita tidak mungkin menampilkan seluruh transkrip dan tema di sini. Ini hanya latihan singkat. Jumlah tema superordinat tidak perlu banyak karena tema superordinat itu sendiri adalah hasil pemadatan. Dalam pengamatan saya sejauh ini, jumlah tema superordinat tidak lebih daripada sepuluh. Jumlah itu tergantung pada kemampuan peneliti memadatkan tema-tema emergen. Bila Anda sudah memiliki transkrip, Anda bisa menjalankan proses di atas secara utuh dari satu partisipan ke partisipan berikutnya. Sekarang, mari kita rangkum perjalanan analisis kita sejauh ini:
transkrip komentar eksploratoris tema emergen tema superordinat
BAB VIII Interpretative Phenomenologial Analisis (IPA): Analisis Data Lanjutan 127
Kotak 8.6 Poin-poin penting dalam pengembangan tema emergen dan superordinat
• Jalankanprosesperumusantemaemergendantemasuperordinatdiatasuntuksatusubjek. Jangan buru-buru pindah ke subjek berikut kalau satu subjek belum selesai.
• Kalauanalisisuntuksatusubjeksudahselesai,simpanhasilnya.Hindarimencocok-cocokkan tema pada satu partisipan dengan partisipan lain. Jangan sampai tema-tema emergen dan superordinat pada partisipan yang pertama dipakai untuk tema-tema emergen dan superordinat untuk partisipan berikutnya. Itu namanya “tidak epochē” dan tidak idiografis. Perlakukan setiap partisipan sebagai pribadi yang unik. IPA menghargai keunikan itu.
• Saatanalisisuntuksatupartisipansudahselesai,adabaiknyauntukmemanfaatkan waktu jedah dengan kegiatan-kegiatan yang merelakskan. Setelah cukup energi untuk kembali menganalisis, ambil transkrip partisipan kedua. Jalankan proses analisis untuk subjek/partisipan kedua persis seperti yang sudah dilakukan untuk transkrip subjek/partisipan pertama. Prosesnya yang sama, tetapi bunyi tema yang ditemukan tidak perlu sama. Abaikan tema-tema emergen dan tema superordinat pada subjek pertama yang sudah selesai dan disimpan. Biarkan transkrip subjek kedua berbicara dalam caranya sendiri.
• JikaAndasudahselesaidenganpartisipankedua,simpanhasilnya.Andakembalibisa memanfaatkan waktu jedah untuk relaksasi. Setelah cukup energi untuk kembali menganalisis, ambil transkrip partisipan ketiga. Jalankan proses analisis yang sama dengan partisipan sebelumnya. Prosesnya yang sama, tetapi bunyi tema yang ditemukan tidak perlu sama. Abaikan tema-tema emergen dan tema superordinat pada partisipan kedua yang sudah selesai dan disimpan. Biarkan transkrip partisipan ketiga berbicara dalam caranya sendiri.
• Begituseterusnyasampaitema-temasuperordinatuntuksemuapartisipansudahditemukan.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup128
C. Tahap Analisis 5: Pola-pola Antarkasus/Antarpengalaman Partisipan
Kalau seluruh subjek sudah dianalisis, kita bisa mencari pola-pola atau jalinan yang ada di antara tema-tema yang sudah kita dapatkan dari seluruh partisipan. Kita tidak perlu tergesa-gesa, apalagi memaksakan jalinan tema-tema itu. Yang kita butuhkan saat ini adalah fokus dan tenang saat memperhatikan seluruh tema dari seluruh partisipan. Dalam keadaan fokus dan tenang itu, kita mau melihat dua hal berikut.
1. Hubungan-hubungan apa yang ada di antara tema-tema itu?2. Tema-tema apa saja yang kelihatan menonjol pada (hampir) semua
partisipan?
Tema Partisipan 1………………………………………………………………
Tema Partisipan 2………………………………………………………………
Tema Partisipan 3………………………………………………………………
Perhatian kita saat ini adalah keterhubungan antartema antarpartisipan.
Kita sekarang ingin melihat pola-pola yang menghubungkan pengalaman dari partisipan-partisipan kita. Istilah yang digunakan Jonathan Smith adalah “pola-pola antarkasus (patterns across cases)”. Istilah “kasus” di sini tidak perlu dikaitkan dengan dengan istilah “kasus” dalam studi kasus. Dalam IPA, setiap pengalaman partisipan adalah pengalaman individual. Pengalaman individual itu diperlakukan sebagai satu kasus yang unik dalam proses analisis. Perhatian akan individu yang unik ini adalah salah satu dari tiga pilar yang menopang bangunan IPA. Ketiga pilar itu sudah kita bicarakan di Bab III.
D. Penataan Seluruh Tema Superordinat
Sampai di sini, kita bisa menganggap bahwa peneliti sudah bergelut dengan perumusan tema dan sudah akrab dengan tema-tema yang muncul pada masing-masing partisipan, baik tema emergen maupun tema superordinat. Perhatikan secara menyeluruh tema-tema yang sudah muncul
BAB VIII Interpretative Phenomenologial Analisis (IPA): Analisis Data Lanjutan 129
dari semua partisipan, baik tema-tema emergen maupun tema-tema super-ordinat. Proses perumusan tema masih perlu kita lanjutkan. Perumusan tema kali ini berfokus pada bagaimana pengalaman partisipan yang satu ter-hubung dengan pengalaman partisipan yang lain. Kita akan merumuskan “tema superordinat antarpartisipan”.
Mari kita memperjelas dengan contoh. Anggap saja kita punya tiga partisipan yang diberi nama dengan inisial A, B, dan C atau nama samaran (pseudonim) Rina, Rini, dan Susi. Inisial dan pseudonim boleh diguna kan, tetapi dalam pengamatan saya sejauh ini, peneliti IPA umumnya menggu-nakan pseudonim. Keterhubungan antarpartisipan bisa dipetakan sebagai berikut.
1. Tema yang keluar pada subjek A (Rina) juga ditemukan pada subjek B (Rini) dan C (Susi). Bunyi temanya tidak harus persis sama, tetapi ada kemiripan di antara ketiganya. Ini berarti kita bisa membuat bunyi tema yang menghubungkan ketiga partisipan. Kita perlu memberi nama baru yang kita anggap cocok untuk menghubungkan kasus/pengalaman partisipan. Tema yang baru ini bukan tema satu partisipan, tetapi tema antarpartisipan yang menghubungkan semua partisipan.
2. Tema yang keluar pada subjek A (Rina) bisa juga ditemukan pada subjek B (Rini), tetapi tidak pada subjek C (Susi). Bukan masalah. Ini berarti kita bisa membuat bunyi tema yang menghubungkan kedua partisipan. Tema yang baru ini bukan tema satu partisipan, tetapi tema antarpartisipan yang menghubungkan beberapa partisipan.
3. Tema tertentu hanya keluar pada subjek A (Rina) dan tidak pada subjek B (Rini) dan C (Susi). Juga bukan masalah. Artinya, tema ini hanya ditemukan pada satu subjek dan tidak dilihat keterhu bungan-nya dengan subjek lain. Dalam kasus seperti ini, kita bisa membuat bunyi tema yang hanya atau cuma ditemukan pada satu partisipan. Tema seperti ini boleh kita sebut sebagai tema distingtif atau tema khusus. Salah seorang mahasiswi, misalnya, melaporkan bahwa dari ketiga partisipannya hanya satu yang mengalami halusinasi.
Jadi, ada tema yang keluar pada semua partisipan, beberapa partisipan, atau hanya satu partisipan. Karena itu, ada baiknya membuat tabel yang
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup130
menunjukkan proses terhubungnya partisipan dalam tema tertentu. Tabel ini namanya “Tabel Induk untuk Tema Semua Partisipan”. Pada tabel itu, kita bisa melihat semua tema superordinat sekaligus bisa menyaksikan bagaimana satu partisipan terhubung dengan partisipan lain. Perhatikan tabel induk berikut ini.
Kotak 8.7 Tabel Induk untuk Tema Semua Partisipan
A. Tema yang terkait dengan kecanduan Baris
Kecanduan sebagai afliksi (derita)Rina : kecanduan itu ibarat hidup yang penuh dengan racun.Rini : Aku di lantai, pipis dan muntah-muntah dan menangisSusi : Aku merasa paranoid dan takut setiap kali aku bangun dan aku
gak tahu aku ada di mana.Mira : Pola makanku udah berantakan.Klara : Aku benar-benar merasa putus asa. Satu-satunya jalan keluar
yang aku pikirin adalah seandainya saja aku bisa bunuh diri.
12398235-236
231332
Intensitas larut ke dalam perilaku adiktif Klara : Aku gak bakal berhenti minum sampai habis atau sampai aku
udah gak sadar lagi.Mira : aku merasa seperti disedot, alkohol menyedot aku.Susi : Aku selalu membawa vodka ke mana aja aku pergi. Rasanya gak
bisa hidup lagi tanpa vodka.Rini : yang aku pengen cuma minum. Pusing amat kata orang atau
apalah.Rina : Aku memaksa minum. Badanku melawan tapi aku tetap aja
minum.
234
143231-232
221
121
Adiksi sebagai dukungan Susi : Cinta pertamaku dan satu-satunya cintaku ya obat sama alkohol.Mira : Aku minum biar perasaan lebih hidup aja. Yulia : Aku gak merasa tenang menghadapi masalahku. Maksudku,
alkohol itulah yang nopang aku saat susah.Klara : Caraku mengatasi masalah ya minum, jadi lebih pede.
132324116-117
142
BAB VIII Interpretative Phenomenologial Analisis (IPA): Analisis Data Lanjutan 131
B. Tema yang terkait dengan pandangan tentang diri Baris
Persepsi tentang diriKlara : Aku kadang-kadang seperti menyalahkan diriku sendiri. Ini gak
bagus lho.Susi : Aku merasa bukan orang yang baik karena aku selalu
membandingkan diriku sendiri dengan orang lain.Rina : Aku gak pernah suka dengan diriku sendiri, gak suka dengan
hidupku. Aku bukan orang yang baik.Rini : Ada pikiran yang bilang aku gak ada apa-apanya, gak ada orang
yang mau peduli sama aku.Yulia : Aku hanya ingin melawan macam-macam emosi yang
mengganggu.
177
234-235
325-326
234-235
223
C. Tema yang terkait dengan relasi Baris
Dinamika hubungan dalam keluargaRina : Ibuku ngenalin aku dengan antidepresan waktu aku masih
remaja … ibuku pecandu.Klara : Ayahku peminum, tapi dia bukan satu-satunya dalam keluargaku
… dia pergi menginggalkan kami.Yulia : Aku mirip dengan ibuku … kami berdua orang yang depresi.Susi : Saudaraku suka minum, sering berantem, kami musuhan.Rini : Aku udah keseringan mabuk dan gak bisa lagi merawat anakku.
Anakku yang lebih gede menjaga yang lebih kecil.
321
112-114
45-4676145-146
Pola-pola dalam hubungan dengan orang lainRina : Menurutku sih, aku memanfaatkan laki-laki saat tidur bareng
mereka… Mungkin karena aku dulunya mengalami pelecehan seksual.
Susi : Cari perhatian, aku senang diperhatikan orang lain.Rini : Aku suka membantu orang lain karena saakuya bisa merasa ada
gunanya.Mira : Aku tidak pengen ketemu orang lain atau melakukan apa pun
dengan orang lain atau berurusan dengan orang lain
78-80
3445
232-233
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup132
D. Tema yang terkait dengan pemulihan Baris
Pemulihan sebagai proses yang sulitRina : gak mudah untuk berhenti. Susi : butuh proses yah buat berhenti.Rini : kamu gak bakal bisa sembuh dengan cepat.Klara : butuh waktu yang lama untuk balik lagi.Mira : masih jauh rasanya kalau pengen berhenti.
12315423124467
Dukungan dalam pemulihanRina : Untuk pertama kali dalam hidupku aku merasa ada orang yang
mengerti aku.Susi : Untuk pertama kalinya aku merasa terharu karena masih ada
yang perhatian sama aku.Rini : Saat hadir dalam pertemuan seperti itu, kamu bisa
mengungkapkan perasaanmu.Yulia : Aku pergi ke tempat olahraga setiap hari karena aku terbantu
dengan depresiku
132
243-244
98
101
Kesadaran-diri dalam pemulihanRina : Aku sekarang sadar aku minum bukan karena aku menikmati,
tapi karena aku melarikan diri.Susi : Aku juga sedang mencoba, mencoba mengerti siapa aku.Rini : Aku benar-benar pengen berhenti minum karena aku tahu aku
gampang kembali lagi.Yulia : Aku mikir dan terus mikir apa sebenarnya yang terjadi sama aku.
342-343
176165
143
Makna pemulihanRina : Aku merasa ada orang yang membersihkan mataku dan aku bisa
melihat lagi.Susi : Rasanya seperti memulai kembali hidup yang baru, benar-benar
baru.Klara : Jalanin hidup yang udah beda banget.Mira : Merasa kembali normalYulia : Dikit dikit kembali bisa menjalani hidup Rini : Dalam lima tahun, mudah-mudahan bisa nikah, mudah-
mudahan bisa punya anak lagi, dan berhenti minum.
143
178
22276432265
BAB VIII Interpretative Phenomenologial Analisis (IPA): Analisis Data Lanjutan 133
Tabel di atas sangat bermanfaat dalam upaya kita menyederhanakan tema superordinat antarpartisipan. Ada sepuluh tema superordinat antarpartisipan. Dalam setiap tema superordinat antarpartisipan itu, kita bisa melihat siapa saja yang terjaring masuk dalam tema itu. Kita tidak hanya menunjukkan orangnya, tetapi juga menunjukkan dengan jelas ucapan intinya dalam transkrip. Ucapan itu bisa dengan mudah ditemukan dalam transkrip dengan menunjukkan pada baris ke berapa dalam transkrip. Itulah manfaat dari penomoran transkrip. Dalam skripsi/tesis/disertasi, tabel ini nantinya masuk dalam Lampiran.
Kadang-kadang ada baiknya juga bila peneliti membuat tema yang menunjukkan frekuensi kemunculan tema pada partisipan. Tabel ini ini disebut “Tabel Identifikasi Tema Berulang”. Perhatikan lagi “Tabel Induk untuk Tema Semua Partisipan” di atas. Sekarang, kita mau mengonversinya menjadi tabel identifikasi tema berulang.
Kotak 8.8 Tabel Identifikasi Tema Berulang
TEMA SUPERORDINAT
Rina Rini Susi Mira Klara Yulia
Lebih dari
setengah sampel?
1 Kecanduan sebagai afliksi (derita)
Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Ya
2 Intensitas larut ke dalam perilaku adiktif
Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Ya
3 Adiksi sebagai dukungan
Tidak Tidak Ya Ya Ya Ya Ya
4 Persepsi tentang diri
Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya
5 Dinamika hubu-ngan dalam keluarga
Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup134
TEMA SUPERORDINAT
Rina Rini Susi Mira Klara Yulia
Lebih dari
setengah sampel?
6 Pola-pola hubungan dengan orang lain
Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya
7 Pemulihan sebagai proses yang sulit
Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Ya
8 Dukungan dalam pemulihan
Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya
9 Kesadaran-diri dalam pemulihan
Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya
10 Makna pemulihan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
Dari tabel identifikasi tema berulang dalam Kotak 8.8, bisa terlihat siapa saja yang terjaring dalam satu tema antarpartisipan. Sebagai contoh, dalam tema superordinat “Pemulihan sebagai proses yang sulit”, ada 5 orang yang terjaring; sementara dalam tema “dukungan dalam pemulihan” dan “kesadaran-diri dalam pemulihan”, ada 4 partisipan yang terjaring. Begitu seterusnya. Tabel ini hanya untuk memberi gambaran tentang distribusi tema pada seluruh partisipan: apakah lebih dari setengah partisipan memilikinya atau tidak? Dalam skripsi/tesis/disertasi, tabel ini nantinya masuk dalam Lampiran.
E. Melaporkan Hasil Analisis
Hasil analisis adalah tema-tema antarpartisipan yang sudah kita temukan. Hasil analisis adalah temuan kita. Kalau kita sudah punya “Tabel Induk untuk Semua Partisipan” dan “Tabel Identifikasi Tema Berulang”, tugas kita menjadi lebih ringan. Kita bisa memajang dua tabel itu di depan meja kerja kita sebagai panduan dalam membuat laporan hasil analisis.
BAB VIII Interpretative Phenomenologial Analisis (IPA): Analisis Data Lanjutan 135
Hasil analisis berarti memberitahukan atau melaporkan temuan kita kepada pembaca dalam cara yang komunikatif. Pemberitahuan atau pelaporan yang komunikatif itu berisi:
Deskripsi dan penafsiran peneliti + Bukti verbatim (harfiah) dalam transkrip
Untuk lebih jelasnya, saya langsung saja memberi contoh yang diambil dari tesis saya yang berjudul “Makna dari Hubungan Syekh-Murid dalam Tarekat Sufi Naqshbandi”. Penelitian ini dilakukan di Inggris dengan mewawancarai tiga guru sufi dari tarekat Naqshbandi. Saya menemukan lima tema superordinat antarpartisipan. Di sini saya hanya mengambil dua tema superordinat antarpartisipan untuk dijadikan contoh.
1. Rasa Syukur atas Kebersamaan dengan Syekh
Seorang syekh di jalan sufi pada dasarnya adalah murid dari syekh yang memandunya. Syekh yang dulunya membimbing juga adalah murid dari seorang syekh. Bila ditelusuri lagi, syekh dari syekh itu juga adalah murid dari syekh sebelumnya. Aliran syekh-murid itu bisa ditelusuri terus ke belakang sampai ke Nabi Muhammad SAW. Seorang syekh adalah saluran bagi mengalirnya ajaran-ajaran spiritual dalam sufisme atau tasawuf. Bagi Abdullah, pengalamannya sebagai murid dari syekhnya adalah pengalaman yang eksklusif dalam pengertian bahwa pendidikan yang ia terima dari syekhnya tidak ditemukan di lembaga pendidikan mana pun yang pernah dia ikuti. Dia mengartikan pendidikan dari syekhnya itu sebagai ajaran-ajaran mengenai kebijaksanaan dan makna hidup, seperti yang dikatakannya berikut ini.
“Saya sudah belajar begitu banyak dari guru spiritualku. Saya sudah mendapatkan eh.. pendidikan sekuler, tetapi pendidikan dari guru spiritualku memberi saya dimensi yang amat sangat berbeda yang tidak diajarkan di mana pun … pendidikan itu tentang kebijaksanaan, tentang apa yang harus diutamakan dalam hidup, tentang mengerti konteks, tahu konteks, punya pemahaman tentang konteks, tahu kebijaksanaan, tahu akan makna keberadaan di dunia .... Ini adalah
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup136
semacam pengetahuan yang saya kira tidak diajarkan di mana pun.”
Farid juga mengungkapkan pengalamannya tentang bagaimana dia sangat mengagumi syekhnya dan bersyukur atas kesempatan untuk menjalani bimbingan spiritual. Ia menggambarkan syekhnya sebagai pribadi yang sangat spesial, menginspirasi, dan kongruen dalam tindakan dan perkataan. Pengalaman dibimbing adalah pengalaman yang sangat membahagiakan dan sangat berkesan. Berikut yang Farid katakan:
“Saya menyadari bahwa syekhku adalah orang yang benar, orang yang bijak, orang yang mulia. Saat saya bertemu dengannya, saya merasa seperti sedang berbicara dengan orang yang sangat sangat spesial, yah.. ehm… seseorang yang memahami saya, seseorang yang mengajari saya persis sama dengan apa yang dia katakan. Dan bila kamu ketemu dengan orang seperti itu, kamu ingin dibimbing. Itu pengalaman yang sangat membahagiakan buatku, pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang menyenangkan.”
Karim juga mengungkapkan bahwa hubungan antara syekh dan murid adalah hubungan pribadi yang dalam. Hubungan ini muncul secara alami karena frekuensi bertemu dengan syekh dalam proses bimbingan. Dalam hubungan itu, tawajjo (perhatian) dari syekh pada murid membantu perkembangan spiritual murid.
“Salah satu tujuan dari sobat (hubungan akrab) adalah murid mendampingi syekh. Semakin sering seseorang bersama syekh semakin dia diingat oleh syekh. Semakin seseorang diingat oleh syekh, semakin besar tawajjo (perhatian) syekh pada orang itu. Tawajjo bukanlah perhatian yang harus terlihat secara fisik. Tawajjo bisa dilakukan di saat dan di tempat di mana murid tidak menyadari bahwa dia sedang menerima tawajjo dari syekhnya.”
BAB VIII Interpretative Phenomenologial Analisis (IPA): Analisis Data Lanjutan 137
2. Membimbing sebagai Tanggung Jawab Amat Besar
Menjadi syekh bukan pilihan karier. Menjadi syekh hanyalah tugas yang diterima begitu saja oleh partisipan ketika syekh mereka membuat keputusan. Keputusan syekh adalah keputusan Allah. Keputusan itu diterima sebagai tanggung jawab yang besar karena terkait dengan tugas yang terhubung dengan Allah. Abdullah mengungkapkan bahwa aktivitasnya dalam membimbing murid adalah tanggung jawab yang ia terima secara spontan tanpa menganggap dirinya sebagai syekh.
“Saya kira tidak seorang pun pantas menjadi pembimbing. Kamu hanya mendapat tugas itu dan kamu menjalankannya dan berharap bahwa Allah menerima apa yang sedang kamu lakukan.”
Karim juga mengungkapkan hal serupa dan menekankan bahwa tugas syekh adalah tugas yang berat dan sulit. Dalam wawancara kami, dia beberapa kali mengulangi bahwa menyesatkan orang lain sangat berisiko bila bimbingan dilihat sebagai pertanggungjawaban syekh kepada Allah kelak. Pertanggungjawaban kelak itu adalah pengingat dalam menjalankan bimbingan. Karena itu, Karim menekankan kehati-hatian dalam membimbing murid.
“Salah satu tantangan yang paling berat adalah menjadi syekh. Banyak orang menganggap menjadi syekh itu gampang. Sebenarnya sangat sulit. Amat sangat sulit. Kenapa begitu? Karena siapa pun bisa gemetar bila memikirkan orang-orang yang sudah saya terima sebagai murid. Ada saatnya nanti saya harus berdiri di depan Allah dan Allah akan menanyai saya tentang mereka.”
Senada dengan Karim, Farid memandang tugasnya dalam mem-bimbing murid sebagai tugas menjalankan kepercayaan dari Allah. Dia melihat tanggung jawabnya sebagai tugas yang membutuhkan pemeriksaan diri dan refleksi diri dalam membimbing murid-murid. Meski demikian, ada rasa bahagia dalam menjalanan tanggung jawab yang besar itu. Kejujuran diri adalah bagian yang penting dalam proses bimbingan.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup138
“Ya, membimbing adalah hal yang luar biasa... saya bahagia bila bisa melayani Allah... membimbing adalah tanggung jawab yang besar. Dan jika kamu menyesatkan seseorang, kamu dinilai untuk perbuatanmu itu. Segala sesuatu yang saya katakan, saya harus berhati-hati. Saya tidak boleh menyesatkan seseorang. Saya tidak boleh tidak jujur atau semacam itu. Saya harus berhati-hati sekali. Membimbing adalah tanggung jawab yang besar dan Allah telah memberikan tanggung jawab itu. Dia mengharapkanmu menjalankannya dengan benar.”
F. Pembahasan
Kita baru saja membicarakan laporan analisis. Setelah melewati laporan analisis itu, kita seharusnya sudah paham pengalaman partisipan. Dengan pemahaman itu, kita berbagi pemahaman dengan orang lain agar orang lain ikut paham. Dalam laporan penelitian, upaya untuk berbagi pemahaman itu disebut pembahasan hasil analisis atau disingkat pembahasan (discussion).
Dalam pembahasan, kita mau menyampaikan temuan kita kepada pembaca dan menempatkannya di tengah literatur yang ada. Di sini kita butuh meninjau kembali literatur yang sudah kita baca yang terkait dengan penelitian kita. Hasil analisis kita bisa sejalan atau tidak sejalan dengan literatur yang tersedia. Bukan masalah jika temuan kita tidak sejalan dengan literatur yang beredar.
Oleh karena itu, peneliti IPA perlu serius menganalisis datanya sekaligus bernyali untuk mengungkapkan hasil analisis bila ada yang khas atau berbeda dari pandangan teoretis yang sedang beredar. Istilah “nyali” di sini tidak berarti bahwa kita ingin menjadi orang yang tampil beda atau eksentrik asal-asalan. Kita hanya ingin mengatakan fakta-fakta apa adanya, berdasarkan apa yang kita temukan dalam pengalaman partisipan. Dalam perspektif fenomenologis, pengetahuan paling dasar bersumber dari pengalaman. Pengetahuan teoretis datang kemudian. Inilah alasan mengapa Husserl menyerukan:
Zurück zu den Sachen selbst! Back to the things themselves!
Kembali ke fakta-fakta itu sendiri!
139
BAB IX
Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Konsep-konsep Filosofis
A. Dua Raksasa Fenomenologis, Dua Pendekatan Fenomenologis
Pembicaraan kita tentang penelitian fenomenologis dalam buku ini sudah separuh jalan. Tujuan khusus kita adalah mengenal dan belajar menggunakan dua versi penelitian fenomenologis dan kita baru saja menyelesaikan salah satu versi penelitian fenomenologis yang cukup populer, yaitu interpretative phenomenological analysis (IPA). Masih ada satu versi penelitian fenomenologis lain yang tersisa, yaitu penelitian fenomenologis deskriptif (PFD). Awalnya, saya ingin langsung membicarakan seperti apa jalannya PFD, tetapi saya merasakan kesulitan karena metode fenomenologis ini sangat kental diwarnai filsafat fenomenologis yang dikemukakan oleh Edmund Husserl, peletak dasar fenomenologi. Bila ditelusuri sejarahnya, PFD yang digagas oleh Amedeo Giorgi memang bertujuan mengembangkan metode penelitian dalam psikologi yang berlandaskan fenomenologi Edmund Husserl.
Bab ini tentang PFD, meski demikian ada baiknya bila kita memperjelas dulu perbedaan antara PFD yang menginduk pada Edmund Husserl dan IPA yang merujuk pada Martin Heidegger. Berkenalan dengan kedua filsuf ini akan sangat membantu dalam memahami perbedaan antara PFD dan IPA. Giorgi (2009) memperkenalkan keduanya sebagai berikut.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup140
Teks Asli
It is fairly well recognized that Edmund Husserl (1859-1938) and Martin Heidegger (1889-1976) were the two giants of phenomenological philosophy during the 20th century …. Husserl was a mathematician, logician, epistemologist, and basically a philosopher interested in grounding theoretical and scientific knowledge .... For Heidegger, the question of being dominated his thinking, and since he traced the question of being back to Dasein, the being who raises the question of being, and discovered that Dasein has to interpret the meaning of being, Heidegger gives priority to interpretation.
Transkreasi
Sudah cukup banyak yang tahu bahwa Edmund Husserl (1859-1938) dan Martin Heidegger (1889-1976) adalah dua raksasa filsafat fenomenologis selama abad ke-20 …. Husserl adalah ahli matematika, logika, dan epistemologi (filsafat ilmu), dan pada dasarnya dia adalah seorang filsuf yang tertarik meletakkan dasar untuk pengetahuan teoretis dan ilmiah …. Bagi Heidegger, persoalan tentang ada mendominasi pemikirannya, dan karena dia menelusuri persoalan tentang ada itu kembali ke Dasein, [yaitu] ada yang mengajukan pertanyaan tentang ada, dan karena Heidegger menemukan bahwa Dasein harus menginterpretasikan makna dari ada, maka Heidegger memprioritaskan interpretasi.
Pernyataan Giorgi di atas mungkin masih terlalu filosofis. Peneliti yang sudah pernah membaca buku tentang fisafat fenomenologis mungkin bisa dengan mudah mengerti maksud dari pernyataan Giorgi itu. Untuk pembaca yang belum familiar dengan buku-buku fenomenologi, saya perlu memperjelas beberapa istilah teknis dalam pernyataan Giorgi itu.
o Logika. Istilah ini berasal dari kata Yunani “logos”. Dalam bahasa Yunani, logos sebenarnya punya banyak arti, seperti kata, gagasan, pikiran, ide, penalaran. Logika adalah cabang dari filsafat yang sibuk dengan penalaran dan penarikan kesimpulan yang benar.
o Epistemologi. Istilah ini berasal dari kata Yunani “epistēmē” yang bisa diterjemahkan “pengetahuan”. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang sibuk dengan teori-teori tentang pengetahuan, khususnya tentang metode yang berkembang dalam ilmu pengetahuan.
BAB IX Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Konsep-konsep Filosofis 141
o Persoalan tentang ada. Filsafat yang secara khusus membicarakan ADA disebut ontologi. Kata Yunani “onto” berarti “ada”. Kita kadang-kadang mendengar pernyatan seperti “Tuhan itu ada”, “Aku berpikir, maka aku ada”, “Bagiku, dia sudah tidak lagi ada”, atau “Ayahnya sudah tidak ada”. Mahasiswa yang ikut kuliah bisa saja ada secara fisik di kelas, tetapi tidak ada secara mental di kelas. Nah, ontologi adalah filsafat yang mengajukan pertanyaan apakah sebenarnya ADA itu? Heidegger tertarik dengan persoalan tentang apa itu ADA? Apa perbedaan antara ada-nya manusia dan ada-nya benda? Manusia makhluk yang spesial karena dia ada sekaligus bisa bertanya tentang ada-nya itu. Benda tidak bisa bertanya tentang ada-nya.
o Dasein. Kita sudah sempat bertemu dengan Dasein ini di Bab III. Dasein adalah manusia dalam pengertian makhluk yang terlempar ke dalam dunia. Di sini saya ingin mengaitkan Dasein itu dengan ADA. Kata Jerman ini sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Da berarti di sana dan Sein berarti ada. Dasein (dibaca dasain dan ditulis dengan huruf awal kapital) secara harfiah berarti “ada di sana”. Dalam buku-buku berbahasa Inggris, Dasein kadang-kadang diterjemahkan there-being (ada-di-sana). Terjemahan ini bisa membingungkan sehingga saya menyarankan untuk mengabaikan segala upaya untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Kita sebaiknya tetap menggunakan istilah “Dasein”. Yang penting kita bisa memahami maksud dari Dasein itu. Dasein dalam fenomenologi Heidegger berarti manusia, tetapi bukan manusia yang umum kita mengerti. Ketika menyebut Dasein, Heidegger sedang menyebut manusia sebagai makhluk yang ber-ADA di dalam dunia sekaligus bisa bertanya tentang keber-ada-annya itu.
o Aku ADA sebagai manusia dan aku bisa bertanya tentang keber-ada-anku sebagai manusia.
o Dalam keber-ada-anku sebagai manusia, aku ada sebagai orang yang disebut dosen oleh mahasiswa-mahasiswa di kampus dan aku bisa bertanya tentang apa artinya keber-ada-an sebagai dosen.
o Dalam keber-ada-anku sebagai dosen psikologi, aku juga ada sebagai terapis dan aku bisa bertanya tentang apa artinya ber-ada-anku sebagai terapis. Begitu seterusnya. Aku ADA dan bisa bertanya tentang ADA-ku.
Saat manusia yang ada mempertanyakan ada-nya sendiri, apa yang dia lakukan? Dia sedang menjalankan interpretasi terhadap ada-nya itu. Karena itu, manusia adalah makhluk yang ada sekaligus repot menginterpretasikan ada-nya sendiri.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup142
Bagi pembaca yang secara khusus ingin tahu lebih dalam dan lebih jauh tentang filsafat fenomenologi dan hubungannya dengan metode penelitian, saya menyarankan Anda untuk membaca buku saya yang lain yang berjudul "Fenomenologi: Filsafat untuk Riset Fenomenologis". Dalam buku itu, saya membicarakan Edmund Husserl dan Martin Heidegger, termasuk beberapa tokoh fenomenologi yang lain. Di sini, kita hanya membicarakan Husserl dan Heidegger sekilas saja.
• Edmund Husserl. Dia adalah Bapak feno-
Gambar 9.1 Edmund Husserl Sumber:pinterest.com
menologi yang kemudian menjadi ki blat PFD. Fenomenologi yang dikembang kan Husserl bertujuan melihat dengan jer nih pengalaman orang lain. Melihat dengan jernih di sini berarti melihat dalam keadaan bebas dari macam-macam teori/prasangka/praduga/asumsi. Untuk bisa melihat de-ngan jernih, seorang peneliti perlu berlatih mem bersihkan dirinya. Caranya ada lah men jalankan epochē. Menjalankan epochē berarti me nyingkirkan macam-macam teori/prasangka/praduga/asumsi yang sudah ber co-kol dalam diri sendiri. Peneliti fenomenologis yang men jalankan epochē secara ketat akan mampu melihat dengan jernih penga laman orang lain. Dengan penglihatan yang jernih itu, peneliti kemudian bisa mendeskripsikan pengalaman partisipan. Demikianlah, PFD ada lah penelitian fenomenologis yang bertujuan mendeskripsikan pengalaman partisipan tanpa tercemari oleh teori/prasangka/pra-duga/asumsi.
• Martin Heidegger. Dia adalah Bapak feno-
Gambar 9.2 Martin Heidegger Sumber:phillwebb.net
menologi kedua sesudah Husserl yang kemu dian menjadi kiblat penelitian IPA. Heidegger sebenarnya adalah murid Husserl. Meski demikian, dia mengem bangkan fe-no me no logi yang menitik berat kan pada inter pretasi/penafsiran. Manusia dan benda itu ada. Saya ada dan kursi yang saya duduki itu juga ada. Kekhasan kita sebagai manusia
BAB IX Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Konsep-konsep Filosofis 143
ada lah ini: manusia itu ada dan sibuk meng inter pretasikan adanya sendiri. Benda juga ada seperti manusia, tetapi benda tidak bisa menginterpretasikan ada-nya. Sejak lahir sampai mati, manusia selalu sibuk menafsirkan macam-macam peristiwa yang dia temui, baik peristiwa di luar dirinya maupun peristiwa di dalam dirinya. Dalam setiap penafsiran, ada pemberian makna. Sebagai peneliti fenomenologis, kita perlu berhati-hati dalam memberi makna. Jika saya bertanya ke Anda: Apa artinya laptop? Maka jawabannya tidak bisa tunggal. Untuk memaknai laptop, kita perlu melihat bagaimana laptop itu terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Makna laptop bagi penulis ber beda dengan makna laptop bagi pembuat animasi. Makna laptop bagi teknisi laptop berbeda dengan makna laptop bagi penjual lap top di toko-toko komputer. Jadi, makna laptop ditentukan oleh bagai mana laptop itu terhubung dengan sekitarnya. Begitu juga dengan partisipan kita dalam penelitian. Saat partisipan bercerita tentang pengalamannya, ceritanya itu terhubung dengan apa dan siapa saja yang dia temui secara pribadi dalam hidupnya. Peneliti feno menologis diharapkan sensitif dengan konteks kehidupan partisi pannya. Beda konteks, beda makna.
Tujuan saya menampilkan kedua tokoh tersebut adalah menunjukkan per-bedaan pandangan di antara dua raksasa fenomenologis. Perbedaan pan dang-an itu telah berdampak pada munculnya dua model penelitian fenomenolo-gis: PFD dan IPA. Keduanya boleh dijadikan metode penelitian. Silakan meneliti dengan menggunakan versi yang Anda minati. Bagi peneliti yang memilih versi IPA, tiga bab sebelumnya (Bab VI - Bab VIII) sudah cukup memberi gambaran tentang apa itu IPA dan bagaimana menjalankan IPA. Penjelasan yang tersisa adalah apa itu PFD dan bagaimana menjalankannya. Baiklah, mari kita fokus ke PFD.
B. Konsep-konsep Filosofis PFD
Di atas saya mengatakan bahwa sulit sekali memahami apa itu metode fenomenologis deskriptif kalau belum berkenalan dengan konsep-konsep kunci dalam pemikiran Edmund Husserl, filsuf yang meletakkan dasar fenomenologi. Oleh karena itu, kita perlu meluangkan sedikit waktu untuk berkenalan dan menjadi lebih akrab dengan beberapa konsep fenomenologis
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup144
Husserl yang relevan bagi PFD. Dalam pengamatan saya, ada enam konsep filosofis yang perlu kita bicarakan untuk memahami PFD, yaitu (1) semboyan fenomenologis, (2) pengalaman langsung, (3) sikap natural versus sikap fenomenologis, (4) reduksi fenomenologis, (5) variasi imajinatif, serta (6) konstitusi dan konstituen.
1. Semboyan Fenomenologis
Edmund Husserl menyerukan dalam bahasa Jerman “Zurück zu den Sachen selbst!”. Seruan itu berarti “Kembali ke fakta-fakta itu sendiri!” atau dalam bahasa Inggris, “Back to the things themeselves!” Inilah prinsip dasar fenomenologis. Kita juga bisa menyebutnya sebagai “semboyan” atau “motto” fenomenologi. Pernyataan yang lebih halus sebagai berikut.
Jerman : Wir wollen auf “die Sachen selbst” zurückgehen.
Inggris : We would like to go back to “the things themselves”.
Indonesia : Kami ingin kembali ke “fakta-fakta itu sendiri”.
Kalimat itu ditulis Husserl untuk pengantar bukunya yang berjudul “Logische Untersuchungen (Logical Investigations/Penelitian-penelitian Logis)”. Mengapa Husserl meminta kita untuk kembali ke fakta-fakta saat melakukan penelitian ilmiah? Husserl menyerukan untuk meninggalkan kebiasaan lama melihat peristiwa dengan menggunakan teori/asumsi/penilaian/dugaan/pra sangka. Dengan menggunakan teori saat melihat pengalaman orang lain, kita sebenarnya melihat pengalaman orang lain secara tidak langsung. Karena penekanan yang langsung pada pengalaman, fenomenologi pada dasarnya nonteoretis.
Jika kita sebagai peneliti melihat pengalaman orang lain dalam keadaan bebas dari teori/asumsi/penilaian/dugaan/prasangka, lalu apa yang terjadi pada kita sebagai peneliti? Peneliti akan berhadapan langsung dengan fakta-fakta (fenomena) tanpa diganggu atau diusik oleh teori/asumsi/penilaian/dugaan/prasangka. Dalam keadaan bebas dari gangguan, kita bisa menggambarkan/mendeskripsikan fakta-fakta apa adanya. Pengalaman orang lain tidak dicemari teori/
BAB IX Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Konsep-konsep Filosofis 145
asumsi/penilaian/dugaan/prasangka. Gambaran/deskripsi apa ada-nya itu adalah deskripsi murni.
Perhatikan istilah “menggambarkan fakta-fakta (fenomena)”. Istilah lainnya adalah mendeskripsikan fakta-fakta (fenomena). Itulah tujuan penelitian fenomenologis deskriptif. Saya perjelas lagi penelitian fenomenologis deskriptif bertujuan memahami pengalaman partisipannya dengan mendeskripsikan fakta-fakta (mental/psikis) yang ditemukan dalam pengalaman partisipan yang orisinal.
2. Pengalaman Langsung (Lived Experience)
Fenomenologi melihat pengalaman manusia sebagai bidang yang menarik untuk diteliti. Dalam literatur berbahasa Inggris, pengalaman langsung ini disebut “lived experience”. Fenomenologi ingin memahami pengalaman langsung (lived experience) itu dengan mengajak peneliti menemukan esensi atau inti dari pengalaman langsung itu. Tulisan van Manen (2005:611) berikut bisa sedikit memperjelas tentang pentingnya mengakses pengalaman bagi fenomenologi.
Teks Asli
Husserl contrasted two modes of givenness of an object in experience: (1) the object as experienced in external perception, such as my house as seen from where I stand, and (2) the object as experienced in internal perception, such as my house as I nostalgically remember it while traveling. The house as perceived from external perception is always seen only from a certain vantage point. It is impossible to see the house in its totality from all possible points of view. And yet the house as object given in internal perception transcends the house that I perceive while standing in front of it. In other words, the house as an object of lived experience
Transkreasi
Husserl membedakan dua cara munculnya objek dalam pengalaman seseorang: (1) objek yang dialami melalui persepsi eksternal, misalnya rumahku yang saya lihat dari posisi tertentu di mana saya berdiri (misalnya, sisi depan atau belakang, sisi kiri atau kanan), dan (2) objek yang dialami melalui persepsi internal, misalnya rumahku dan macam-macam kenangan di dalamnya yang muncul dalam ingatanku saat saya pergi jauh dari rumah. Rumah yang muncul lewat persepsi luar hanya terlihat dari sudut pandang tertentu (depan, belakang, samping kiri, atau samping kanan).
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup146
is given in its essence. When I think of my house, I don’t just think of it as perceived from the front, the side, the back, or some other vantage point. Rather, I “see” the house as intuitively given as a house, in all its many exterior and interior aspects, meanings, and significations. Phenomenology as transcendental reflection goes beyond the object as naively seen through empirical perception. Husserl is especially concerned with how we come to know what appears in consciousness as living experience.
Kita tidak mungkin melihat keseluruhan rumah dari macam-macam sudut pandang (sekaligus). Rumah yang muncul dalam persepsi internal (gambaran mental) saya melebihi rumah yang saya lihat ketika saya sedang berdiri di depan rumah. Dengan kata lain, esensi dari rumah muncul lewat pengalaman langsung akan rumah.
Pengalaman langsung itu adalah pengalaman mental. Dalam setiap pengalaman langsung (pengalaman mental) pasti ada esensi. PFD dirancang untuk membantu kita menemukan esensi dari pengalaman langsung itu. Sekarang perhatikan judul penelitian fenomenologis berikut yang bisa ditelusuri di Google.
A descriptive phenomenological study of the lived experience of homosexual men coming out within the institution of marriage
Studi fenomenologis deskriptif tentang pengalaman langsung pria homoseksual yang secara terbuka menyatakan identitas seksualnya dalam institusi pernikahan
The lived experience of compassion as described by adult mindfulness meditation meditators: A phenomenological study
Pengalaman langsung tentang Welas-asih (compassion) sebagaimana yang dideskripsikan oleh meditator dewasa yang menjalankan meditasi berkesadaran penuh (mindfulness): Sebuah studi fenomenologis
The lived experience of recovering from addiction: a phenomenological study
Pengalaman langsung sembuh dari kecanduan: Studi fenomenologis
BAB IX Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Konsep-konsep Filosofis 147
Cara membunyikan judul penelitian PFD cukup bervariasi dan kita sudah membicarakan ini di Bab 4. Meski judul bisa dibunyikan beragam, sorotan utamanya adalah the lived experience (pengalaman langsung).
3. Sikap Natural versus Sikap Fenomenologis
Kita baru saja membicarakan bagaimana fenomenologi menggam-barkan pengalaman tanpa menggunakan teori, tetapi langsung ke pengalaman itu sendiri. Masalahnya, peneliti sebagai ilmuwan tidak bisa lepas dari bacaan-bacaan teoretis. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah mungkin bagi peneliti untuk melihat langsung fakta-fakta dalam keadaan bebas dari pengaruh pandangan teoretis? Bisa saja, tetapi harus diakui tidak mudah. Kita butuh kerja keras membersihkan diri dari kebiasaan melihat dengan asumsi dan teori. Dalam fenomenologi, orang yang melihat fakta dengan teori/prasangka/praduga/asumsi/peni-laian disebut orang yang melihat dengan sikap natural. Sikap natural ini adalah lawan dari sikap fenomenologis. Jadi, ada dua sikap dalam fenomenologi.
1. Sikap natural (natural attitude), yaitu sikap sehari-hari keba-nyakan orang yang masih berada dalam kendali asumsi, teori, dugaan, hipotesis, dan sejenisnya. Sikap inilah yang ditunjukkan partisipan kita saat menceritakan pengalaman hidupnya.
2. Sikap fenomenologis (phenomenological attitude), yaitu sikap yang lepas dari kekangan asumsi, teori, dugaan, hipotesis, dan se je nisnya. Sikap inilah yang seharusnya ditunjukkan oleh pene liti fenomenologis saat mendengarkan dan menganalisis pengalaman hidup partisipannya.
Metode ilmiah yang disuarakan fenomenologi memang berbeda dari metode yang berkembang dalam ilmu-ilmu alam (natural sciences). Dalam ilmu-ilmu alam, kita dibiasakan melihat kejadian atau peristiwa dengan asumsi dan teori yang sudah berkembang. Teori-teori itu umumnya diterima sebagai alat bantu dalam memahami suatu peristiwa atau kejadian. Peran teori seperti itu wajar dalam ilmu alam. Bagaimanapun, ilmu tentang manusia (human sciences) tidak bisa disamakan dengan ilmu
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup148
tentang alam (natural sciences). Untuk itu, fenomenologi hadir untuk menawarkan metode bagi ilmu-ilmu kemanusiaan.
4. Reduksi Fenomenologis
Seperti yang baru saja kita lihat, manusia pada umumnya hidup dalam sikap natural. Fenomenologi yang dikembangkan Husserl mengajak kita untuk bergeser dari sikap natural menuju sikap fenomenologis. Pengembangan sikap fenomenologis terkait dengan apa yang oleh Husserl disebut reduksi fenomenologis. Reduksi fenomenologis berarti upaya mengurangi apa saja yang bukan inti dari pengalaman. Pada saat Anda mencari Atha di tengah kerumunan banyak orang, Anda akan mereduksi yang bukan Atha. Anda melihat orang itu, “Ah, bukan Atha”. Anda lalu melihat orang lain lagi, “Ah bukan Atha” sampai akhirnya Anda menemukan, “Ini dia Atha”. Pada saat Anda mencari handphone Anda dalam kamar, Anda akan memperhatikan semua benda di kamar dan mereduksi benda-benda lain yang bukan handphone Anda.
Reduksi fenomenologis berjalan serupa. Peneliti ingin menemukan inti dari pengalaman dengan menjalankan reduksi fenomenologis. Sikap dasar yang diperlukan dalam menjalankan reduksi fenomenologis adalah epochē. Kita perjelas lagi epochē ini dengan memperhatikan penjelasan Jochen Dreher (2015) berikut ini.
Teks Asli
What Husserl denotes as phenomenological reduction is also called “phenomenological” or “transcendental epoché.” What is being achieved with this methodological procedure is the “bracketing” or “inhibition” of the world; assumptions and previously constituted knowledge are bracketed with the help of phenomenological reduction.
Transkreasi
Istilah “reduksi fenomenolgis” yang dikemukakan Husserl juga dikenal dengan istilah “epochē fenomenologis” atau “epochē transendental”. Apa yang didapatkan dari proses metodologis (proses epochē) ini adalah “mengurung” atau “menghambat” dunia sekitar; asumsi-asumsi dan pengetahuan yang sudah ada dalam diri kita dikurung (disingkirkan) dengan bantuan reduksi fenomenologis.
BAB IX Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Konsep-konsep Filosofis 149
Masih cukup sering terjadi bahwa peneliti fenomenologis memak-sakan teori dalam analisisnya. Dalam beberapa penelitian fenomenologis di Indonesia, saya menemukan bahwa saat menganalisis data, peneliti cenderung mencocokkan atau menggandengkan pernyataan partisipan dalam transkrip dengan teori yang dipelajarinya. Gaya analisis seperti itu belum mencerminkan sikap fenomenologis. Fenomenologi itu kekuatan-nya ada pada epochē. Pernyataan partisipan dalam penelitian harus dijaga keasliannya dengan membersihkan diri sendiri. Teori dan macam-macam pengetahuan yang bukan dari partisipan dikesampingkan dulu. Jika peneliti ingin melihat hubungan pernyataan partisipan dengan teori, maka itu urusan pembahasan (discussion), bukan analisis.
5. Variasi Imajinatif (Imaginative Variation)
Semakin jelas sekarang bahwa fenomenologi bergerak menuju inti dari pengalaman. Untuk bisa menangkap inti pengalaman, peneliti perlu mengembangkan sikap fenomenologis dengan berlatih menjalankan epochē. Masih ada aktivitas lain yang juga diperlukan agar bisa sampai pada inti dari pengalaman, yaitu variasi imajinatif. Istilah “imajinasi” di sini bukan imajinasi liar atau yang kita sebut fantasi atau khayalan. Imajinasi di sini adalah imajinasi yang dijalankan dalam keadaan epochē.
Saat masuk ke pengalaman seseorang, peneliti bisa bertemu dengan macam-macam ciri dari pengalaman. Sebagai contoh, ketika peneliti masuk ke pengalaman cuci darah, maka orang yang mengalami cuci darah akan bercerita banyak tentang pengalamannya menjalani cuci darah. Dalam keadaan epochē, kita bertanya: Apa inti dari pengalaman cuci darah? Untuk menemukan inti itu, kita menjalankan variasi imajinatif. Dengan menjalankan variasi imajinatif, peneliti mengurangi atau menyingkirkan macam-macam ciri atau karakteristik yang bukan merupakan esensi dari fenomena. Kita mengamati macam-macam ciri yang muncul sambil bertanya pada diri sendiri: Apakah ciri ini mutlak ada dalam pengalaman partisipan? Jika tidak mutlak ada, kita bisa menyingkirkannya. Sebaliknya, jika mutlak ada, itulah inti dari pengalaman.
Kita perjelas lagi dengan mengambil buah apel sebagai contoh. Kita ingin paham esensi atau inti dari buah apel. Kita mengamati buah apel
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup150
dan salah satu ciri yang keluar adalah warna merah. Kita melihat warna merah itu sambil bertanya: “Apakah warna merah ini mutlak ada untuk disebut apel?” Apel tidak hanya berwarna merah. Ada yang berwarna hijau dan ada juga yang berwarna jambon. Artinya, warna merah dari apel tidak mutlak ada sehingga warna merah bukan inti dari apel. Kita lalu mencoba lagi melihat ciri-ciri yang lain sampai bertemu dengan ciri yang mutlak ada pada apel. Demikianlah, variasi imajinatif bertujuan menemukan hal berikut:
"Karakteristik/ciri yang mutlak ada bagi fenomena. Tanpa karakteristik/ciri itu, fenomena tidak ada."
Ada empat tahapan yang kita lalui dalam menjalankan variasi imaji natif, yaitu: (1) pilih pengalaman yang ingin Anda perhatikan, (2) perhatikan pengalaman itu dalam keadaan epochē, (3) dengan imajinasi (dalam keadaan epochē) biarkan macam-macam ciri-ciri dari fenomena muncul, dan (4) renungkan ciri yang mutlak ada bagi fenomena.
Variasi imajinatif ini berperan penting saat menjalankan PFD. Peneliti-peneliti yang sudah terlatih mengembangkan variasi imajinatif secara alamiah mengembangkan kemampuan mengintuisi. Ya, mengintuisi, bukan menganalisis. Istilah “intuisi” dalam fenomenologi berbeda dari intuisi yang dimengerti awam. Intuisi di sini berarti, peneliti yang berada dalam keadaan epochē bisa menangkap langsung inti dari pengalaman partisipan.
Latihan ber-epochē adalah latihan menjalankan variasi imajinatif dan menghidupkan intuisi. Saya teringat dengan sahabat senior saya Profesor Darmanto Jatman, penulis yang aktif dalam menganalisis macam-macam persoalan sosial dan politik dari perspektif budaya Jawa. Pada suatu saat menjelang usia pensiunnya, dia mengatakan kepada saya, “Semakin ke sini, saya semakin percaya pada intuisi.” Saya kira, pengalamannya yang panjang dalam menganalisis, mengembangkan epochē, dan menjalankan variasi imajinatif telah membuka keran intuisi dalam dirinya.
Saat kita sebagai peneliti PFD ingin melakukan analisis terhadap data (transkrip), kita akan mendeskripsikan pengalaman partisipan. Dari
BAB IX Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Konsep-konsep Filosofis 151
deskripsi itu, kita kemudian menemukan tema-tema. Dari sekian ba nyak deskripsi dan tema, kita perlu menentukan tema-tema mana saja yang esensial dan yang bukan esensial. Dalam menjalankan PFD, peneliti diharapkan bisa berjalan semakin dekat ke eidos (intisari/esensi) dari pengalaman partisipan. Untuk berjalan semakin dekat ke eidos, kita perlu epochē, variasi imajinatif, dan intuisi.
6. Konstitusi dan Konstituen
Sebelum membicarakan apa itu konstitusi dan konstituen, saya ingin menampilkan dulu dua konsep yang saling terkait erat dalam fenomenologi, yaitu (1) noesis dan (2) noema. Coba pikirkan “eksnara-pidana yang mengalami penolakan keluarga” pasca-pembebasan dari lem baga pemasyarakatan. Kita persingkat lagi: Ada eksnarapidana yang mengalami penolakan keluarga. Kita pecah lagi menjadi dua: (1) ada eksnarapidana yang meng-alami dan (2) penolakan keluarga yang di-alami. Noesis adalah [orang] yang meng-alami dan noema adalah [sesuatu] yang di-alami. Eksnarapidana yang mengalami adalah noesis dan penolakan keluarga yang dialami adalah noema. Noesis dan noema itu selalu ada bersama. Dalam bahasa filsafat, noesis dan noema itu koeksisten.
Analisis fenomenologis pada dasarnya adalah upaya menganalisis noesis karena kita ingin mengerti apa yang terjadi pada [orang] yang mengalami (noesis). Kita ingin mengerti noesis dalam hubungannya dengan noema. Oleh karena itu, analisis fenomenologis bisa juga kita sebut sebagai analisis noetik. Peneliti fenomenologis memperhatikan betul peristiwa/kejadian mental pada partisipan sebagai orang yang menga lami. Partisipan dalam penelitian fenomenologis adalah noesis yang pasti punya noema. Contoh-contoh dalam Kotak 9 memperjelas lagi hubungan noesis dan noema.
Kotak 9.1 Hubungan Noesis-Noema
Presiden Dekan Mahasiswa
mendengarkan memimpin mendengarkan
keluhan masyarakat rapat dosen ceramah dosen
noesis/subjek/yang mengalami
noema/objek/ yang dialami
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup152
Saat memperhatikan orang yang mengalami suatu peristiwa, kita akan melihat bahwa orang yang mengalami itu memberi arti untuk sesuatu yang dialaminya. Dalam contoh tadi, eksnarapidana yang mengalami penolakan keluarga (noesis) memberi arti untuk penolakan dari keluarga yang dialaminya (noema). Nah, pemberian arti pada noema itu disebut konstitusi. Konstitusi terjadi secara alamiah pada orang yang mengalami sesuatu. Eksnarapidana yang mengalami penolakan keluarga secara alami bisa mengonstitusi (memberi arti untuk) peristiwa penolakan dari keluarga yang dialaminya.
Sampai di sini cukup diingat bahwa setiap orang mengonstitusi (memberi arti untuk) peristiwa yang dia alami. Saat menganalisis data dalam PFD, kita masuk ke dalam pengalaman partisipan-partisipan kita dan mencoba menemukan tema-tema penting dalam konsitusi yang mereka lakukan. Tema-tema penting yang keluar dari konstitusi yang dilakukan oleh partisipan-partisipan kita disebut konstituen. Oleh karena itu, istilah “tema” dalam PFD kadang-kadang juga disebut “konstituen”.
------------------------------------------------------------
Semua konsep-konsep di atas perlu dimengerti terlebih dahulu oleh peneliti fenomenologis yang ingin menjalankan PFD. Proses analisis data dalam PFD terkait erat dengan semua konsep itu. Oleh karena itu, pastikan bahwa Anda memahami konsep-konsep di atas sebelum menjalankan analisis data. Nah sebelum Anda berpindah ke bab selanjutnya yang secara khusus membicarakan analisis data, saya berharap Anda sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.
1. Mengapa Husserl menulis “Kami ingin kembali ke fakta-fakta itu sendiri”?
2. Bagaiman hubungan fenomenologi dengan pengalaman langsung?
3. Apa perbedaan antara sikap natural dan sikap fenomenologis?
4. Apa itu epochē ?
5. Apa itu variasi imajinatif dan manfaatnya bagi “aktivasi intuisi”?
6. Apa itu konstitusi dan konstituen?
BAB IX Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Konsep-konsep Filosofis 153
Jawaban untuk semua pertanyaan tersebut penting untuk melakukan PFD. Jika ada dari pertanyaan-pertanyaan itu yang belum bisa Anda jawab, Anda sebaiknya memantapkan lagi bacaan Anda tentang bab ini. Bab selanjutnya adalah penerapan dari yang telah kita pelajari dalam bab ini.
155
BAB X
Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Analisis Data
Bila kita sudah akrab dengan beberapa konsep penting dalam fenomenologi yang dikemukakan Husserl di Bab IX, maka memahami metode penelitifan fenomenologis deskriptif menjadi lebih mudah. Fokus kita dalam bab ini adalah alur analisis data dalam PFD. Sebelum sampai ke situ, saya ingin menyegarkan kembali salah satu poin penting dalam fenomenologi Husserl.
Jika kita sebagai peneliti bisa melihat pengalaman orang lain dalam keadaan bebas dari teori/asumsi/penilaian/dugaan/prasangka, lalu apa yang terjadi pada kita sebagai peneliti? Peneliti akan berhadapan langsung dengan fenomena (peristiwa/kejadian/aktivitas mental) tanpa diantarai teori/asumsi/penilaian/ dugaan/prasangka. Dalam keadaan bebas dari “perantara” itu, pengalaman orang lain tidak dicemari teori/asumsi/penilaian/dugaan/prasangka. Kita bisa menggambarkan/mendeskprisikan fakta-fakta apa adanya. Gambaran/deskripsi yang apa adanya itu adalah deskripsi murni (pure description).
Aktivitas inilah yang diharapkan menjadi agenda utama dari peneliti yang ingin menjalankan PFD. Peneliti diminta untuk menetralkan dirinya sendiri dari macam-macam pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya, seperti teori, asumsi, penilaian, dugaan, prasangka. Netralisasi diri seperti itu
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup156
adalah langkah awal dalam menjalankan analisis fenomenologis deskriptif. Istilah untuk netralisasi diri itu adalah epochē.
Maka itu, bila ada yang bertanya, “Apakah pilar dari PFD?”, saya kira, jawabannya adalah adalah epochē. Bila epochē bisa dijalankan, maka pengalaman orang lain bisa dilihat dengan jernih dan apa adanya. Saat pengalaman orang lain terlihat jernih dan apa adanya, maka tugas peneliti selanjutnya adalah mendeskripsikan penglihatannya yang jernih dan apa adanya itu. Ada cukup banyak literatur yang beredar tentang penelitian fenomenologis yang berbasis Husserl. Kita tidak mungkin membicarakan semuanya di sini. Secara pribadi, saya menganjurkan dua buku berikut untuk dijadikan referensi induk bagi PFD dalam bidang psikologi.
Giorgi, A. (2009). The descriptive phenomenological method in psychology: A modified Husserlian approach. Pittsburgh, PA: Duquesne University Press
Moustakas, Clark. (1994). Phenomenological research methods. London: Sage.
Dalam seluruh proses penelitian fenomenologis deskriptif, epochē selalu menjadi “cahaya pemandu” dalam beraktivitas. Tujuan dari epochē adalah menjaga peneliti dari kecenderungan melihat pengalaman orisinal partisipan dengan menggunakan teori, penilaian, atau gagasan tertentu. Mari kita perhatikan dahulu cerita Barbro Giorgi (2010:119) berikut ini tentang perjalanan akademisnya mengenal fenomenologi.
Teks Asli
As I embarked on my studies in psychology, I was frustrated by my experience which could be simplistically summarized by “but it’s not like that”. All the theories I read in the textbooks held together beautifully as long as they remained on the page but the minute I tried to take them into “life” and tried to
Transkreasi
Di awal kuliah psikologiku dahulu, saya merasa jengkel ketika pengalamanku dikatakan “bukan begitu [karena tidak sesuai teori]”. Semua teori yang saya baca dalam buku-buku ajar terangkai begitu indah selama masih berada dalam halaman buku, tetapi ketika saya
BAB X Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Analisis Data 157
use them in order to understand myself or to understand others around me and our relationship to one another, the beautiful logic of the theory would collapse to one degree or another with me saying to myself “but it doesn’t work that way”.
This frustration continued all through graduate school and, I think culminated in the literature review for my dissertation. From the very beginning of my education I experienced a gap between what I was being taught about psychology, and life as I experienced it.
mencoba [mengeluarkannya dari buku dan] menerapkannya dalam “hidup” dan berusaha menggunakannya untuk memahami diriku sendiri atau untuk memahami orang lain di sekitarku dan hubungan kami satu sama lain, logika yang indah dari teori itu rontok dalam beberapa hal dan saya mengatakan pada diriku sendiri “bukan begitu”.
Frustrasi itu berlanjut di sepanjang masa studi S1 dan, saya kira memun-cak pada saat saya menyusun reviu literatur untuk disertasiku. Sejak awal pendidikanku, saya merasakan jurang antara apa yang diajarkan kepadaku tentang psikologi dan kehidupan sebagaimana yang saya alami.
Tidak ada salahnya belajar tentang macam-macam teori dalam psiko-logi, tetapi fenomenologi mengingatkan kita untuk menjaga diri dari kecenderungan melihat pengalaman orang lain berdasarkan pengetahuan yang sudah bersarang dalam diri kita. Ada kemungkinan bahwa teori cocok dengan pengalaman dan ada kemungkinan bahwa teori itu tidak cocok. Dalam kutipan di atas, Barbro Giorgi sedang mengatakan sesuatu yang penting dalam fenomenologi, yaitu epochē saat mendengarkan dan memaknai pengalaman orang lain.
Untuk itu, bisa dimengerti mengapa epochē begitu sentral dalam fenomenologi. Dalam beberapa kali kesempatan berdiskusi, saya mendapat pertanyaan yang bagus: “Apakah manusia memang bisa membersihkan dirinya dari teori, anggapan, penilaian, atau prasangka yang sudah terlanjur bersarang dalam dirinya?” Sebagai peneliti, kita tetap membaca teori dan memahaminya. Daya mengingat dan daya berpikir analitis yang kita miliki adalah anugerah. Kita tetap menerima pandangan teoretis dari tulisan pakar-pakar yang kita baca. Peneliti hanya mengurung teori saat mendengarkan dan
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup158
menganalisis pengalaman orang lain. Singkat kata, peneliti fenomenologis itu nonteoretis, bukan antiteori.
Hanya dalam kondisi epochē, analisis fenomenologis deskriptif bisa dijalankan. Menjalankan epochē adalah agenda utama peneliti fenomenologis. Jika epochē harus kita jalankan, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah menjalankan epochē? Epochē itu urusan pribadi. Setiap peneliti punya tugas mengenali kencenderungan-kecenderungan dalam dirinya yang potensial mengotori pengalaman partisipan. Dalam konteks kehidupan pribadi, situasi tenang dibutuhkan untuk menunjang proses epochē. Dalam konteks kehidupan akademis, peneliti terlebih dahulu perlu dikenalkan dengan filsafat fenomenologis sebelum melakukan penelitian fenomenologis.
PFD adalah penelitian yang sangat kental diwarnai filsafat fenomenologis sehingga pembaca yang sudah akrab dengan filsafat fenomenologis akan mudah memahami konsep-konsep kunci dalam penelitian fenomenologis dan prosedur analisis yang dijalankan. Beberapa dari konsep-konsep kunci itu sudah kita bicarakan di Bab 9. Bersyukur bahwa fakultas-fakultas psikologi di Indonesia memasukkan mata kuliah “fenomenologi dan eksistensialisme” dalam kurikulum pengajaran. Harus diakui bahwa menemukan pengajar “fenomenologi yang khusus untuk psikologi” adalah tantangan tersendiri dalam psikologi. Tantangan itu perlu diterima demi dasar-dasar yang kokoh untuk penelitian fenomenologis. Jika penelitian kuantitatif butuh mata kuliah statistika sebagai dasar, maka penelitian fenomenologis butuh mata kuliah fenomenologi sebagai dasar.
Untuk PFD, Anda tidak dituntut memahami fenomenologi sebagai filsafat, tetapi memahami bagaimana fenomenologi diterapkan di dalam penelitian psikologis. Saya kira, beberapa konsep kunci dalam fenomenologi Husserl yang sudah kita bicarakan di bab sebelumnya sudah cukup untuk menjadi pengetahuan dasar dalam menjalankan PFD. Lagi pula, PFD yang dicanangkan oleh Amedeo Giorgi memang dimaksudkan untuk berkiblat pada fenomenologi Edmund Husserl.
BAB X Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Analisis Data 159
A. Amedeo Giorgi dan Fenomenologi Deskriptif
Amedeo Giorgi mengembangkan model analisis fenomenologis yang oleh banyak kalangan dianggap pengembangan langsung dari ajaran Husserl dan dimodifikasi untuk penelitian psikologis. Beberapa konsep pokok dari Husserl tetap digunakan dalam menjalankan analisis. Untuk lebih jelasnya, saya kutipkan langsung apa yang dikatakan Giorgi (2009:64) tentang metode Husserl.
Teks Asli
Husserl ’s method involves three steps: (a) One assumes the transcendental phenomenological attitude, (b) one brings to consciousness an instance of the phenomenon to be explored, whether actual or fictional, and with the help of free imaginative variation, one intuits the essence of the phenomenon being investigated, and (c) one carefully describes the essence that has been discovered.
Transkreasi
Metode Husserl meliputi tiga tahap: (a) peneliti mengembangkan sikap fenomenologis transendental dengan menjalankan epochē , (b) peneliti menyadari munculnya ciri/karakteristik dari fenomena (peristiwa mental/kejadian mental) yang diteliti, baik itu ciri/karakteristik yang nyata atau fiktif saja. Dengan bantuan variasi imajinatif, peneliti melihat semua ciri/karakteristik yang muncul dan mengintuisi esensi/inti dari fenomena (pengalaman) yang diteliti, dan (c) peneliti berhati-hati mendeskripsikan esensi/inti dari apa yang sudah ditemukan.
Metode Husserl itu bisa kita urutkan sebagai berikut.
Menjalankan epochē menyaksikan macam-macam ciri/karakteristik dari fenomena menjalankan variasi imajinatif mengintuisi inti/esensi dari fenomena mendeskripsikan tema inti/esensi dari fenomena
Menurut Giorgi, metode yang dikembangakan filsuf Husserl itu bisa ditarik ke dalam psikologi dengan sedikit modifikasi agar sesuai dengan tuntutan-tuntutan ilmiah yang berkembang dalam psikologi. Inilah yang
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup160
diupayakan Giorgi: Memodifikasi metode filosofis Husserl untuk penelitian psikologis. Kutipan berikut adalah gambaran modifikasi yang dilakukan Giorgi (2009:65). Jika ada kesulitan dalam memahami terjemahan berikut, Anda bisa langsung membaca transkreasi.
Teks Asli
The modifications to be added to the Husserlian method for psychological purposes are (a) the descriptions to be analyzed are obtained from others, who remain within the natural attitude, but the researcher does assume the phenomenological psychological reduction, (b) one tries to determine the psychological essence of the phenomenon rather than its philosophical essence—or, the psychological perspective is adopted first and then the essence, or the most invariant meaning structure for a specific context, is determined with respect to that perspective—(c) the imaginative variations that are employed are done in dialogue with the empirical variations that are given in the descriptive data, and (d) the eidetic structure that is discovered and described is considered to be typical rather than universal. All of the modifications that are mentioned are responses to the demands of contemporary scientific practices.
Terjemahan
Metode Husserl bisa dimodifikasi un-tuk tujuan psikologis sebagai berikut:
a. deskripsi pengalaman yang akan di-analisis didapatkan dari orang lain yang berada dalam sikap natu ral, tetapi peneliti dalam keadaan men-jalankan reduksi psikologis feno me-no logis,
b. peneliti berusaha menentukan esensi (inti) psikologis dari feno-mena [pengalaman] yang dite-liti dan bukan lagi esensi (inti) filosofisnya–atau peneliti meng-gunakan dahulu perspektif psiko-logis nya dan kemudian dengan perspektif psikologis itu, peneliti menemukan inti/esensi (struktur yang paling invarian) dari penga-laman partisipan dalam konteks tertentu (tujuan dan pertanyan penelitian),
c. variasi imajinatif (lihat Bab ) yang digunakan dilakukan dalam hu-bung an dengan variasi empiris yang disajikan dalam data deskriptif, dan
d. struktur eidetik [tema inti] yang ditemukan dan dideskripsikan ada-lah struktur [tema] yang tipikal alih-alih struktur [tema] yang universal.
BAB X Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Analisis Data 161
Semua modifikasi tersebut merupakan respons terhadap tuntutan-tuntutan keilmiahan [dalam psikologi] saat ini.
Transkreasi
a. Partisipan menceritakan pengalamannya kepada peneliti dalam sikap natural dan peneliti psikologis berusaha memahami pengalaman partisipannya dalam sikap fenomenologis dengan menjalankan epochē. Sikap natural dan sikap fenomenologis ini sudah kita bicarakan di Bab IX.
b. Sebagai peneliti fenomenologis yang berlatar belakang psikologi, kita ingin menemukan inti psikologis dari pengalaman partisipan, bukan inti filosofis. Giorgi menekankan istilah “inti psikologis” untuk menegaskan bahwa penelitian fenomenologis yang dia rancang adalah penelitian untuk peneliti psikologis. Peneliti dalam psikologi adalah peneliti yang tumbuh dalam komunitas psikologi sehingga wajar jika peneliti menggunakan perspektif/cara pandang psikologis yang sudah membentuknya secara akademis. Peneliti menggunakan perspektif psikologisnya, bukan menggunakan teori-teori psikologis. Perspektif psikologis itu digunakan oleh peneliti psikologis dalam proses menemukan inti dari pengalaman partisipan yang sedang ditelitinya.
c. Setelah melihat pengalaman orisinal partisipan dengan perspektif psikologis, peneliti menjalankan variasi imajinatif (lihat Bab IX). Peneliti akan menemukan macam-macam peristiwa mental dalam pengalaman partisipan dan mendeskripsikan pengalaman itu. Variasi imajinatif akan membantu peneliti menentukan peristiwa mental yang esensial dan yang tidak esensial.
d. Buah dari variasi imajinatif itu adalah ditemukannya struktur inti (tema inti) dari pengalaman partisipan yang sedang diteliti.
Modifikasi yang dilakukan Giorgi itu adalah upaya untuk menyesuaikan metode filosofis Husserl dengan tuntutan-tuntutan metodologis yang berkembang dalam psikologi.
B. Prosedur Analisis Data ala Giorgi
Giorgi tidak memberikan proses tahapan analisis yang jelas. Namun kita bisa menemukan tahapan analisis yang digunakan Giorgi lewat penelitian fenomenologis yang ia lakukan tentang belajar. Dalam penelitian itu,
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup162
pertanyaan pokoknya adalah: Apa makna dari belajar? Setelah mewawancarai partisipan, hasil wawancara (transkrip) kemudian dianalisis. Berikut prosedur analisis yang ditempuh Giorgi (1975b:74-75).
Teks Asli
1. The researcher reads the entire description straight through to get a sense of the whole. A phenomenological interpretation of this process would be that the researcher is present to the situation being described by the subject by means of imaginative variation ….
2. The researcher reads the same description more slowly and delineates each time that a transition in meaning is perceived with respect to the intention of discovering the meaning of learning (the research example discussed). After this procedure one obtains a series of meaning units or constituents ….
3. The researcher then eliminates redundancies, but otherwise keeps all units. He then clarifies or elaborates the meaning of the constituents by relating them to each other and to the sense of the whole ….
4. The researcher reflects on the given constituents, still expressed essentially in the concrete language of the subject, and transforms the meaning of each unit from the everyday naive language of the subject into the language of psychological science insofar as it is revelatory of the
Transkreasi
1. Peneliti membaca seluruh deskripsi (transkrip) untuk mendapatkan cita rasa keseluruhan dari transkrip. Pada tahap ini, penafsiran fenomenologis dilakukan dengan masuk ke dalam dunia kehidupan (situasi kehidupan) partisipan lewat transkrip. Alat bantu untuk masuk ke dalam dunia kehidupan partisipan adalah variasi imajinatif ….
2. Peneliti membaca deskripsi (transkrip) yang sama pelan-pelan. Saat membaca, peneliti akan merasakan pergeseran makna. Peneliti memberi tanda setiap kali ada pergeseran makna pada transkrip. Dengan memberi tanda pada transkrip, peneliti mendapatkan unit-unit makna atau konstituen-konstituen.
3. Peneliti memeriksa lagi unit-unit makna pada transkrip dan menyingkirkan unit-unit makna yang redundan (tidak relevan dengan pertanyaan penelitian). Peneliti kemudian membaca lagi seluruh unit makna dan melihat saling keterkaitan di antara unit-unit makna.
BAB X Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Analisis Data 163
phenomenon of learning …. It is at this point that the presence of the researcher is most evidently present ….
5. The researcher then synthesizes and integrates the insights achieved into a consistent description of the structure of learning. The structure is then communicated to other researchers for purposes of confirmation or criticism.
4. Konstituen-konstituen (unit-unit makna) kemudian dirumuskan ulang oleh peneliti dengan menggunakan bahasa yang sedekat mungkin dengan bahasa partisipan. Selanjutnya, unit-unit makna yang sudah dirumuskan ulang itu ditrans formasikan ke dalam bahasa psiko logis. Pada tahap ini, latar belakang keilmuan peneliti menjadi jelas.
5. Peneliti kemudian menyintesiskan dan mengintegrasikan tema-tema psikologis yang ditemukannya. Hasil sintesis atau integrasi itu kemudian dideskripsikan sebagai tema-tema pokok dari belajar (topik penelitian Giorgi). Tema-tema pokok itu kemudian dikomunikasikan ke peneliti-peneliti lain untuk dikonfirmasi atau dikritik.
Proses analisis yang dilakukan Giorgi di atas bisa menjadi landasan kita dalam menjalankan analisis data dalam PFD ala Giorgi. Berikut ini adalah lima tahapan dalam analisis fenomenologis deskriptif yang bisa kita gunakan dalam mengikuti alur analisis ala Giorgi.
1. Peneliti mengembangkan sikap fenomenologis
Sikap dasar kebanyakan orang adalah sikap natural, yaitu melihat pengalaman dengan teori, asumsi, penilaian, dugaan, atau sejenisnya. Sikap natural itu adalah kecenderungan umum dalam melihat suatu fenomena (peristiwa mental). Seorang peneliti fenomenologis deskriptif dituntut untuk bisa menggeser sikap natural menjadi sikap fenomenologis. Sikap fenomenologis bisa dimiliki dengan berlatih epochē yang dalam bahasa Inggris disebut bracketing (mengurung asumsi, teori, penilaian, dugaan,
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup164
dan sejenisnya). Giorgi (1994) menjelaskan epochē/bracketing itu sebagai berikut.
Teks Asli
A process whereby one simply refrains from positing altogether. One looks at the data with the relative attitude of openness.
Transkreasi
[Epochē adalah] Proses di mana kita hanya menghentikan kebiasaan berasumsi. Kita melihat data dengan sikap yang relatif terbuka.
Demikiankah, peneliti berusaha membuka dirinya selebar mungkin dan senetral mungkin terhadap informasi yang keluar dari pengalaman orang lain. Dalam sikap mental yang terbuka dan netral itu, data-data akan berbicara kepada peneliti. Inilah yang dimaksud Edmund Husserl lewat semboyan “zu den Sachen selbst! (Biarkan fakta-fakta berbicara sendiri)”. Intinya, mantapkan diri dahulu dengan komitmen untuk epochē sebelum masuk ke analisis transkrip.
2. Peneliti berulang kali membaca transkrip
Transkrip adalah tampilan tertulis dari pengalaman partisipan. Transkrip adalah data empiris yang dimiliki peneliti fenomenologis. Istilah “empiris” berarti bersumber langsung dari pengalaman. Kita perjelas dahulu:
Istilah “empiris” berasal dari kata Yunani “empeiria” yang berarti pengalaman. Transkrip bersumber langsung dari pengalaman (empeiria) partisipan. Karena itu, transkrip adalah data empiris.
Oleh karena itu, peneliti fenomenologis harus akrab dahulu dengan datanya yang empiris itu. Keakraban itu secara alami terbentuk bila peneliti membaca berkali-kali seluruh naskah. Dalam istilah Giorgi, manfaat yang didapatkan dari membaca serius transkrip adalah kita bisa “get a sense of the whole experience (merasakan pengalaman partisipan secara menyeluruh)”. Dalam tahap ini, peneliti berhadap-hadapan dengan transkrip dan merasakannya secara keseluruhan.
BAB X Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Analisis Data 165
3. Peneliti membuat unit-unit makna atau satuan-satuan makna (meaning units)
Pada tahap ini, kita membaca kembali transkrip. Jika sebelumnya, kita hanya membaca untuk merasakan seluruh transkirip, maka sekarang, kita membaca transkrip sekaligus memaknainya. Bila peneliti sungguh-sungguh mengalir bersama transkrip, dia bisa merasakan pernyataan-pernyataan yang perlu diberi makna dan yang tidak perlu diberi makna. Untuk setiap pernyataan yang bermakna, kita bisa memberi tanda dengan pensil atau polpen berwarna. Kita juga bisa menggunakan garis miring (/) untuk memisahkan satu pernyataan bermakna dari pernyataan lain. Tidak ada ketentuan pasti kapan satu makna berakhir dan bagaimana memberinya tanda. Sejauh kita larut ke dalam transkrip, pergeseran makna itu akan terasa. Ini mirip dengan pengemudi yang bisa merasakan kapan harus mengeser gir saat sedang berkendaraan. Semua bagian transkrip yang kita beri tanda dengan pensil warna/polpen warna/garis miring disebut unit-unit makna (satuan-satuan makna).
4. Peneliti mentransformasikan unit-unit makna ke dalam deskripsi yang sensitif secara psikologis
Apa itu deskripsi yang sensitif secara psikologis? Peneliti psikologi adalah peneliti yang keilmuannya berlatar belakang psikologi. Oleh karena itu, peneliti psikologi punya sensitivitas atau kepekaan untuk memberi makna psikologis untuk unit-unit makna. Pada tahap keempat ini, peneliti mentransformasikan unit-unit makna ke dalam deskripsi psikologis. Kita tidak mengubah unit-unit makna dari ucapan partisipan tetapi mengekspresikannya ulang dalam bahasa psikologis. Transformasi unit makna menjadi pemaknaan psikologis butuh variasi imajinatif. Unit-unit makna yang tidak relevan dengan judul atau pertanyaan penelitian (redundan) dibuang saja.
5. Peneliti membuat sintesis untuk deskripsi psikologis
Penelitian fenomenologis berjalan menuju esensi/inti dari pengalaman. Artinya, ada proses pengerucutan dari informasi yang begitu banyak dalam transkrip menjadi deskripsi psikologis. Pada tahap kelima ini, kita tetap menggunakan variasi imajinatif untuk mengerucutkan atau
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup166
menyaring lagi deskripsi psikologis. Peneliti melihat saling keterhubungan di antara deskripsi-deskripsi psikologis yang sudah diberikan. Saling keterhubungan itu kemudian memunculkan (mengeksplikasi) tema-tema esensial dalam pengalaman partisipan. Tema-tema esensial itu kadang-kadang disebut juga “tema-tema invarian” atau “struktur-struktur invarian”. Silakan memilih istilah yang Anda rasa cocok. Yang penting adalah peneliti paham proses analisis mulai dari transkrip sampai pada tema-tema esensial. Ada saatnya seluruh tema esensial (tema invarian/struktur invarian) diintegrasikan atau disintesiskan atau disatukan dan peneliti diharapkan bisa menyaksikan “yang paling esensial di antara yang esensial”. Itulah eidos (inti) dari pengalaman partisipan.
Proses di atas bisa dibuatkan skema sebagai berikut.
Epochē transkrip unit-unit makna deskripsi psikologis eksplikasi (pemunculan) tema-tema esensial (tema-tema invarian/struktur-struktur invarian) sintesis seluruh tema esensial menemukan eidos (inti pengalaman).
C. Prosedur Analisis Data ala Moustakas
Clark Moustakas adalah seorang psikolog klinis yang menerapkan fenomenologi dalam praktik klinisnya. Dalam bukunya yang berjudul “Phenomenological Research Methods (Metode-metode Penelitian Fenomeno-logis)”, Moustakas (1994) memberikan langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam menjalankan analisis data versi PFD. Moustakas menawarkan model analisis yang dimodifikasi dari beberapa sumber. Moustakas menawarkan dua model analisis, yaitu: (1) model analisis fenomenologis yang dimodifikasi dari metode van Kaam dan (2) model analisis yang dimodifikasi dari metode Stevick, Colaizzi, dan Keen. Berikut ini, saya akan menampilkan alur utama dalam menganalisis model yang kedua: Metode Stevick-Colaizzi-Keen.
BAB X Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Analisis Data 167
1. Peneliti menjalankan epochē
Dalam bab sebelumnya, kita bertemu dengan dua macam sikap, yaitu (1) sikap natural dan (2) sikap fenomenologis. Di sini, peneliti ingin meninggalkan sikap natural menuju sikap fenomenologis. Apa artinya memiliki sikap fenomenologis? Memiliki sikap fenomenologis berarti menjalankan epochē. Mari kita simak apa yang ditulis Moustakas (1994:85) tentang epochē.
Teks Asli
In the Epochē , we set aside our prejudgments, biases, and preconceived ideas about things. We “invalidate”. “inhibit”, and “disqualify” all commitments with reference to previous knowledge and experience (Schmitt, 1968, p. 59). The world is placed out of action, while remaining bracketed. However, the world in the bracket has been cleared of ordinary thought and is present before us as a phenomenon to be gazed upon, to be known naively and freshly through a “purified” consciouness ....
Transkreasi
Dalam epochē, kita mengesampingkan praanggapan (prapenilaian), macam-macam bias (prasangka), dan gagasan-gagasan yang sudah terbentuk sebe-lum nya tentang apa saja. Kita “tidak membenarkan”, “menghambat”, dan “menyingkirkan” semua komitmen yang terkait dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah terlanjur bercokol dalam diri kita. Dunia tidak dihilangkan, tetapi hanya dimasukkan dalam kurung (disingkirkan sejenak). Dunia dalam kurung itu dibersihkan dari pikiran biasa (pikiran dalam sikap natural) dan dihadirkan di depan kita sebagai fenomena yang menjadi pusat perhatian (diperhatikan dengan sikap fenomenologis). Fenomena itu diperhatikan dengan naif (apa adanya) dan dilihat dengan segar melalui kesadaran yang “dimurnikan” [dari pengaruh macam-macam pengetahuan yang sudah bercokol dalam diri sendiri] ....
Epochē itu perlu dilatih dengan niat yang betul-betul kuat untuk menetralkan diri. Peneliti fenomenologis mau berlatih menyingkirkan
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup168
macam-macam parasangka, pandangan teoretis, dan penilaian tentang fenomena yang selama ini sudah terbentuk. Singkatnya, peneliti ingin melihat dengan mata yang segar, mata seorang pemula. Jika aku sebagai peneliti bisa melihat dengan mata segar, maka aku disebut “aku yang transendental (transcendental I)”. Tetapi bila mataku belum segar, maka aku disebut “aku empiris (empirical I)”. Latihan epochē adalah latihan mentransformasikan aku yang empiris (belum ber-epochē) menjadi aku yang transendental (sudah menjalankan epochē).
2. Peneliti menjalankan reduksi fenomenologis
Kita perhatikan dulu apa yang ditulis Moustakas (1994:97) berikut ini.
Teks Asli
To summarize, the steps of Phenomenological reduction include: Bracketing, in which the focus of the research is placed in brackets, everything else is set aside so that the entire research process is rooted solely on the topic and question; horizonalizing, every statement initially is treated as having equal value. Later, statements irrelevant to the topic and question as well as those that are repetitive or overlapping are deleted, leaving only the Horizons (the textural meanings and invariant constituents of the phenomenon); Clustering the Horizons Into Themes; and Organizing the Horizons and Themes Into a Coherent Textural Description of the Phenomenon.
Transkreasi
Sebagai rangkuman, langkah-langkah dalam reduksi fenomenologis meliputi: (1) bracketing (istilah Ing-gris untuk epochē), di mana fokus pene litian diletakkan dalam kurung (ditepikan dahulu), segala sesuatu yang lain disingkirkan sehing ga selu ruh penelitian hanya dilandasi topik dan pertanyaan [yang ingin ditemukan jawabannya]; (2) melaku-kan horizonalisasi yang berarti semua pernyatan awal partisipan diang-gap memiliki bobot yang sama. Selan jut nya, pernyataan-pernyatan yang tidak relevan dengan topik dan per tanyaan penelitian dan juga pernyataan-pernyataan yang berulang dan tumpang tindih dihapus saja sehing ga yang tersisa hanya horizon-horizon (makna-makna tekstural dan konstituen-konstituen invarian/tetap);
BAB X Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Analisis Data 169
(3) mengelompokkan horizon-horizon (makna tekstural dan konsti tuen-konstituen yang invarian) men jadi tema-tema; dan (4) mengatur hori-zon-horizon (makna tekstural dan konstituen-konstituen) dan tema-tema menjadi deskripsi tekstural yang menyeluruh.
Sepertinya pernyataan Moustakas tentang reduksi fenomenologis di atas sudah cukup jelas. Ada empat tahap dalam proses reduksi itu.
a. Dengan menjalankan epochē, peneliti membaca seluruh transkrip berkali-kali agar bisa merasakan transkrip secara menyeluruh.
b. Peneliti menjalankan horizonalisasi dengan melihat bahwa seluruh pernyataan partisipan sama pentingnya. Kita diminta untuk ber-sikap adil pada seluruh transkrip. Mengapa digunakan istilah “hori-zonalisasi”? Bila Anda duduk di tepi pantai memandang ke laut bebas tanpa ada objek yang menarik perhatian (gunung, sunset, burung-burung yang terbang), apa yang Anda lihat? Anda melihat horizon (cakrawala) dengan adil dan tanpa diskriminasi. Nah, dalam horizonalisasi, kita bersikap adil dan nondiskriminatif dalam melihat seluruh transkrip. Semua pernyataan dalam transkrip sama pentingnya. Ada saatnya pernyataan disaring. Saat penyaringan berjalan, ada pernyataan yang ditampung dan ada yang dibuang. Pernyataan yang dibuang antara lain:
o pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan penelitian,
o pernyataan yang tumpang tindih,o pernyataan yang berulang.
Pernyataan-pernyataan yang tersisa setelah dibuang disebut horizon-horizon. Dengan kata lain, horizon-horizon adalah pernyataan-pernyataan yang terkait dengan pertanyaan pokok penelitian kita.
c. Peneliti kemudian mengelompokkan horizon-horizon itu menjadi tema-tema.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup170
d. Akhirnya, peneliti membuat deskripsi untuk tema-tema yang dida-patkan. Deskripsi untuk tema-tema itu disebut deskripsi tekstural.
3. Peneliti menjalankan variasi imajinatif
Pada tahap ini, deskripsi tekstural ditransformasikan (diubah) menjadi deskripsi struktural. Peneliti masuk semakin dalam ke dunia makna di balik transkrip. Untuk bisa menjalankan transformasi (peru-bahan) itu, peneliti perlu mengembangkan variasi imajinatif. Berikut yang dikatakan Moustakas tentang variasi imajinatif (1994:97).
Teks Asli
Following Phenomenological Reduction, the next step in the research process is that of Imaginative Variation. The task of Imaginative Variation is to seek possible meanings through the utilization of imagination, varying the frames of reference, employing polarities and reversals, and approaching the phenomenon from divergent perspectives .....
Transkreasi
Setelah menjalankan reduksi fenomenologis, langkah selanjutnya dalam proses penelitian adalah manjalankan variasi imajinatif. Dalam variasi imajinatif, tugas peneliti adalah mencari makna-makna apa saja yang mungkin [keluar dari pengalaman partisipan] dengan menggunakan imajinasi, melihat macam-macam variasi makna, melihat perbedaan dan pertentangan, dan mendekati fenomena dari macam-macam perspektif ….
Variasi imajinatif itu dijalankan dalam keadaan epochē. Jadi, bukan khayalan atau fantasi yang digerakkan secara liar oleh alam bawah-sadar. Dengan variasi imajinatif itu, kita memusatkan perhatian pada deskripsi tekstural dan melihat deskripsi tekstural itu dari macam-macam sudut pandang dan macam-macam kemungkinan. Hasilnya adalah makna-makna struktural. Makna struktural ini adalah makna yang sudah dekat dengan inti dari pengalaman. Jadi, deskripsi tekstural bisa menjadi deskripsi struktural karena variasi imajinatif.
BAB X Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Analisis Data 171
4. Peneliti membuat sintesis deskripsi tekstural dan struktural
Pada tahap ini, peneliti menggabungkan deskripsi tekstural dan deskripsi struktural yang sudah didapatkan dari seluruh partisipan. Jadi, ada semacam upaya memperlihatkan “benang merah” dari seluruh partisipan. Umumnya, peneliti menampilkan seluruh deskripsi dalam narasi peneliti plus bukti potongan transkrip. Harapan dari penggabungan itu adalah peneliti bisa bisa menemukan esensi dari pengalaman. Nah, esensi ini adalah tujuan terdalam dari PFD. Moustakas (1994:100) mengatakan begini.
Teks Asli
The final step in the phenomenological research process is the intuitive integration of the fundamental textural and structural descriptions into a unified statement of the essences of the experience of the phenomenon as a whole. This is the guiding direction of the eidetic sciences, the establisment of a knowledge of essences (Husserl, 1931, p. 44). Essence, as Husserl (1931) employs this concept, means that which is common or universal, the condition of quality without which a thing would not be what it is (p. 43).
Transkreasi
Tahap terakhir dalam proses penelitian fenomenologis (deskriptif ) adalah penyatuan intuitif dari semua deskripsi tekstural dan struktural yang penting menjadi pernyataan tentang esensi dari pengalaman partisipan tentang fenomena secara menyeluruh…. Dalam pandangan Husserl, esensi adalah sesuatu yang umum atau universal, [esensi adalah] kondisi atau kualitas yang bila hilang, maka sesuatu bukan sesuatu.
-----------------------------------------------------
Penemuan esensi adalah tujuan terdalam dari PFD. Esensi seharus-nya adalah tema yang mengikat semua partisipan. Artinya, semua partisipan sepakat bahwa esensi yang ditemukan peneliti memang adalah bagian paling penting dari pengalaman hidup mereka. Esensi selalu ada di balik pengalaman partisipan. Tidak mudah menemukan esensi ini karena butuh refleksi yang mendalam terhadap tema-tema tekstural dan struktural. Kita, misalnya, bertanya: apakah esensi dari kuliah bagi mahasiswa psikologi?
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup172
Kita lalu mewawancarai beberapa mahasiswa. Satu mahasiswa mungkin menjawab bahwa kuliah baginya berarti kesempatan berorganisasi. That’s fine. That’s okay. Mereka mengalaminya. Tapi, apakah berorganisasi harus ada untuk disebut kuliah? Tidak harus ada. Berarti berorganisasi bukan esensi dari kuliah. Ada juga yang menjawab bahwa kuliah baginya adalah kesempatan belajar berkelompok. That’s fine. Tetapi apakah belajar kelompok harus ada untuk disebut kuliah? Tidak juga. Ada juga yang iseng menjawab bahwa dia punya kesempatan berpacaran. That’s okay. Tapi apakah harus ada? Tidak juga. Mahasiswa lain menjawab bahwa kuliah baginya adalah kesempatan menyerap informasi dari literatur yang dibutuhkan untuk mengerti jiwa. Apakah penyerapan informasi dari literatur itu harus ada untuk disebut kuliah? Iya, harus ada. Artinya, penyerapan informasi ilmiah adalah penting bagi kuliah. Apa gunanya powerpoint cantik, kalau tidak ada penyerapan informasi? Apa gunanya ruang kuliah dengan smart TV di empat sudut kalau tidak ada penyerapan informasi? Apa gunanya tiga dosen mengajar sekaligus dalam satu ruang kalau tidak ada penyerapan informasi? Apa manfaatnya praktikum tanpa penyerapan informasi? Tanpa penyerapan informasi oleh mahasiswa, kuliah menjadi bukan kuliah. Apakah kita bisa mengatakan bahwa penyerapan informasi dari literatur oleh mahasiswa mutlak ada dalam kuliah? Jika ya, maka penyerapan informasi oleh mahasiswa adalah esensi dari kuliah.
Bagaimana peneliti bisa menangkap esensi? Jalankan epochē dan variasi imajinatif. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tentang kuliah di atas adalah contoh variasi imajinatif. Apa yang membuat peneliti bisa menangkap esensi? Jawabannya mungkin sedikit mengagetkan. Peneliti bisa menangkap esensi dengan intuisi. Ya, dengan intuisi. Analisis fenomenonologis deskriptif pada akhirnya bermuara pada intuisi. Harus diakui bahwa istilah “intuisi” ini sering dimengerti secara keliru di kalangan awam dan, saya kira juga, di kalangan ilmuwan. Dalam fenomenologi, intuisi bisa bekerja baik saat kita bersungguh-sungguh menjalankan epochē dan variasi imajinatif. Dalam bab selanjutnya, kita akan kembali membicarakan intuisi ini lebih jauh lagi. Yang penting dalam bab ini, kita bisa paham mengapa dalam kutipan di atas,
BAB X Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Analisis Data 173
Moustakas mengatakan bahwa intuitive integration (integrasi intuitif ) diperlukan agar peneliti bisa sampai pada esensi.
------------------------------------------
Sebagai penutup bab ini, saya ingin menampilkan tiga alur analisis dalam penelitian fenomenologis deskriptif yang cukup sering digunakan. Urutan masing-masing alur analisis memang berbeda, tetapi semuanya bersumber dari fenomenologi Husserl yang menekankan epochē. Anda cukup memperhatikan bagaimana alur analisis itu bergerak menuju inti (eidos) pengalaman tanpa harus terganggu dengan perbedaan istilah.
Kotak 10.1 Perbandingan Tiga Alur Analisis PFD
Alur Analisis Data
Versi Giorgi (1975) Versi Colaizzi (1978) Versi Moustakas (1994)
• Penelitimengembang-kan sikap fenomeno-logis dengan mulai menjalankan epochē.
• Penelitimembacatranskrip untuk mendapatkan cita rasa keseluruhan transkrip.
• Penelitimembuatunit-unit makna.
• Penelitimentransfor-masikan unit-unit makna menjadi des-krip si yang sensitif secara psikologis untuk masing-masing partisipan.
• Dalamkeadanepochē, peneliti membaca secara menyeluruh dan mendalam transkrip wawancara untuk me ra sakan individu dan latar belakang kehidupannya.
• Penelitimengidentifi-kasikan pernyataan-pernyataan signifikan yang terhubung lang-sung dengan fenomena yang diteliti.
• Penelitimengembang-kan makna interpretif (makna lewat penaf-sir an) untuk setiap per nya taan yang signifikan.
• Penelitimenjalankanepochē.
• Penelitimembacatranskrip berkali-kali sampai akrab.
• Penelitimenjalankanreduksi fenomenologis dengan epochē, horizonalisasi, pengelompokan tema, dan deskripsi tekstural.
• Penelitimenjalankanvariasi imajinatif untuk memunculkan deskripsi struktural dari deskripsi tekstural untuk masing-masing partisipan.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup174
• Penelitimembuatsin tesis (penyatuan) untuk seluruh deskripsi (yang sensitif secara psikologis).
• Penelitisampaipadaesensi dari pengalaman seluruh partisipan.
• Penelitimengelom-pok kan makna-makna interpretif menjadi tema-tema. Tema-tema berulang dan tidak sesuai dengan perta nyaan penelitian disingkirkan saja.
• Tema-temakemudiandiintegrasikan da lam bentuk deskripsi me-nye luruh. Tema-tema yang dideskripsikan di kuatkan dengan transkrip wawancara.
• Penelitimembuatper-nyataan singkat dari deskripsi menyeluruh dan menampilkan per-nyataan funda men tal yang meru pakan esen-si dari pengalaman seluruh partisipan.
• Pernyataanfundamen-tal itu kemudian dicek kebenarannya dengan menyampaikannya pada partisipan. Jika ada ketidaksesuaian dengan pengalaman partisipan, peneliti kem bali lagi ke tahap identifikasi per nya-taan-pernyataan signifikan (tahap kedua di atas).
• Penelitimembuatsintesis untuk deskripsi tekstural dan deskripsi struktural untuk seluruh partisipan.
• Penelitisampaipadaesensi dari pengalaman seluruh partisipan.
175
BAB XI
Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Descriptive Phenomenological Analysis (DPA)
A. Membedakan Analisis PFD dari IPA
Dengan berakhirnya Bab X, kita sudah menuntaskan pembicaraan tentang proses analisis data dalam PFD dan IPA. Kedua versi penelitian fenomenologis itu pada dasarnya sepakat tentang perlunya menjalankan epochē. Meski demikian, keduanya berbeda dalam cara menjalankan epochē. Peneliti yang menggunakan PFD terlebih dahulu berkomitmen menjalankan epochē sebelum menjalankan analisis terhadap transkrip. Hasil yang diharapkan dari epochē itu adalah peneliti mampu melihat fenomena dengan jelas. Dengan penglihatan yang jernih itu, peneliti kemudian mendeskripsikan fenomena dan menangkap intinya. Dalam IPA, epochē berjalan bersama secara dinamis dengan proses menginterpretasikan fenomena yang sedang diteliti. Artinya, dunia pengalaman peneliti dibiarkan bertemu dengan dunia pengalaman partisipan. Dalam pertemuan itu, peneliti terus-menerus mengoreksi dirinya atau merevisi dirinya sampai muncul pemahaman.
Di samping itu, PFD dan IPA juga memperlihatkan perbedaan dalam melaporkan hasil analisis data. PFD berfokus pada pengalaman yang umum di antara partisipan (shared experience) sehingga bisa dimengerti mengapa data bergerak dari transkrip menuju tema-tema esensial (invarian) sebelum akhirnya sampai pada esensi dari pengalaman semua partisipan. IPA tidak berfokus pada pengalaman yang umum, tetapi pada pengalaman individual dan personal sehingga tidak ada upaya untuk sampai pada esensi atau inti
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup176
dari pengalaman. Untuk lebih jelasnya, saya kutipkan saja apa yang ditulis oleh Jonathan A Smith dkk (2009; 200-201) tentang perbedaan antara PFD dan IPA.
Teks Asli
Because of the different emphases between Giorgi’s phenomenological psychology and IPA, the outcome of research using the two approaches tends to look rather different. The result of a Giorgi study is most likely to take the form of a third person narrative, a synthesized summary statement outlining the general structure for the phenomenon under question. The result of an IPA analysis usually takes the form of a more idiographic interpretative commentary, interwoven with extracts from the participants’ accounts.
Transkreasi
Karena penekanan-penekanan yang berbeda antara psikologi fenomenologis Giorgi (PFD) dan IPA, hasil penelitian yang menggunakan dua pendekatan ini cenderung agak berbeda. Hasil dari penelitian Giorgi sangat mungkin berbentuk narasi orang ketiga [peneliti bernarasi tentang partisipan], penyataan rangkuman hasil sitensis yang menjadi dasar untuk struktur umum (esensi) dari fenomena yang diteliti. Hasil dari IPA biasanya berbentuk komentar interpretatif idiografis (komentar peneliti untuk pernyataan pribadi partisipan), yang dikaitkan dengan esktrak dari cerita-cerita partisipan.
Meski berbeda, baik PFD maupun IPA pada dasarnya adalah penelitian fenomenologis. Kita tidak perlu terjebak dalam kubu fenomenologi interpretatif atau kubu fenomenologi deskriptif. Prinsip yang mendasari semua penelitian fenomenologis adalah upaya memahami pengalaman langsung partisipan. Perbedaan jalur yang ditempuh bukan masalah sejauh bisa dipertanggungjawabkan di depan masyarakat ilmiah. Karena itu, lebih baik mengatakan penelitian fenomenologis deskriptif “dan” fenomenologis interpretatif alih-alih penelitian fenomenologis deskriptif “versus” fenomenologis interpretatif.
B. Descriptive Phenomenological Analysis (DPA)
Pada tahun 1970-an, Amedeo Giorgi mengembangkan bentuk pene-litian fenomenologis yang awalnya dikenal sebagai penelitian eksistensial-
BAB XI Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Descriptive Phenomenological Analysis (DPA) 177
fenomenologis dan sekarang umum dikenali sebagai penelitian fenomenologis deskriptif (PFD). Pengembangan itu dilakukan di Universitas Duquesne. Ada beberapa versi PFD yang berkembang, seperti versi Giorgi, versi Colaizzi, versi van Kaam. Dari beberapa versi itu, versi Giorgi adalah versi yang umum dikenal. Sebenarnya, Giorgi sendiri tidak mengklaim bahwa versi yang dia kembangkan adalah versi terbaik. Setiap peneliti diberi kebebasan untuk menentukan versi yang dianggap cocok untuk dijalankan. Giorgi (1975a:83) menulis sebagai berikut.
Teks Asli
... the method we are using as a demonstration … should not be considered paradigmatic for all phenomenologically based research. It should be taken for what it is, one example of the application of phenomenology to psychology ….
Transkreasi
… metode yang kami tunjukkan tidak seharusnya dianggap paradigmatis (di-ja di kan panduan pokok) untuk semua penelitian yang berbasis pada feno-me no logi. Metode kami diterima saja sebagai metode, sebagai satu contoh dari penerapan fenomenologi bagi psikologi ….
Jelas bahwa PFD tidak memiliki model analisis data yang satu untuk semua. Setiap peneliti dibiarkan kreatif mengembangkan dan memodifikasi metode sejauh berbasis pada fenomenologi Husserl. Dalam bab ini, saya ingin menambahkan satu model analisis PFD yang kami kembangkan dan diberi nama descriptive phenomenological analysis (DPA).
C. Alur Analisis Data dalam DPA
The meaning is not on the phrase ... it is the totality of what is said ... it is given with the words for those who have ears to hear.
Makna tidak melekat pada kata-kata ... makna itu adalah keseluruhan dari apa yang dikatakan ... Makna itu diberikan dengan [bantuan] kata-kata bagi orang yang punya telinga untuk mendengarkan.
Maurice Merleau-Ponty
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup178
Alur analisis ini adalah pengembangan dari PFD versi Giorgi yang dihubungkan dengan gagasan-gagasan pokok dalam fenomenologi Husserl. Sejalan dengan apa yang baru saja dikatakan filsuf fenomenologi Maurice Merleau-Ponty, penelitian fenomenologis seharusnya bergerak dari seluruh ucapan partisipan dalam transkrip menuju makna inti dari seluruh ucapan partisipan. Dalam alur itulah, DPA berjalan. Mari kita lihat perjalanan itu tahap demi tahap.
1. Langkah pertama adalah membaca transkrip berkali-kali. Transkrip adalah pengalaman partisipan dalam bentuk tertulis. Masuk ke dalam transkrip berarti masuk ke dalam pengalaman partisipan. Ada dua tahap awal yang penting dalam memasuki transkrip.
• Dalamkeadaanepochē, peneliti membaca transkrip berkali-kali sampai merasakan cita rasa seluruh transkrip. Transkrip ori-sinal ini bisa kita sebut sebagai deskripsi natural karena masih merupakan ekspresi asli (ekspresi natural) dari partisipan. Pada tahap ini, peneliti hanya membaca transkrip orisinal dalam keadaan relaks, fokus, dan mencoba untuk menyelaraskan diri dengan pikiran, perasaan, dan emosi partisipan.
• Setelahmenangkaptranskripsecarakeseluruhan,penelitimem-baca transkrip sambil mengalir dalam transkrip. Ini juga dilaku-kan dalam keadaan epochē. Peneliti membaca transkrip sambil “meraba tekstur” dari transkrip. Peneliti memberi tanda setiap kali dia merasakan perubahan tekstur. Tanda itu bisa berupa garis miring (/) atau superskrip (1, 2, 3, dan seterusnya). Setiap pernyataan yang berada di antara garis miring/superskrip disebut unit makna (satuan makna). Bila seluruh transkrip sudah diberi tanda, maka transkrip siap untuk dianalisis. Dalam contoh berikut, saya memilih menggunakan tanda superskrip.
BAB XI Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Descriptive Phenomenological Analysis (DPA) 179
Kotak 11.1 Penghayatan Transkrip dan Pembentukan Unit Makna
Transkrip/Deskripsi Natural Transkrip/Deskripsi Natural
Peneliti hanya membaca seluruh transkrip
Baca sampai tuntas dan hayati
Peneliti membaca dan merasakan tekstur transkrip
Hayati transkrip dan beri tanda satuan-satuan makna
Lebih jauh tentang itu eh … gak tahu gimana yah eh… menurutku sih itu terjadi karena aku, aku, aku gimana yah, aku gak ngerti aja kenapa aku bisa begitu waktu itu saat aku terima diagnosis HIV. Aku gak bisa aja berhenti memikirkannya dan em … aku harus melewati masa itu dan em rasanya seperti harus belajar lagi mengenal diriku sendiri. Orang-orang yang kenal aku pasti tahu kondisiku. Aku capek banget… banget … capek dengan pikiranku sendiri. Aku mikirin pikiran mereka tentang aku. Mereka Pasti tahu ada yang salah sama aku. Aku paranoid. Mereka bakal tahu tentang kondisiku. Aku berusaha menutupi dan berusaha tampil seperti orang yang gak hidup dengan HIV tapi gak mungkin karena semakin kamu berusaha berhenti mikirin, semakin sering pikiran itu mengganggu.. Yah.. seperti itulah.
Lebih jauh tentang itu eh … gak tahu gimana yah eh… menurutku sih itu terjadi karena aku, aku, aku gimana yah, aku gak ngerti aja kenapa aku bisa begitu waktu itu1 saat aku terima diagnosis HIV. Aku gak bisa aja berhenti memikirkannya2 dan em … aku harus melewati masa itu dan em rasanya seperti harus belajar lagi mengenal diriku sendiri.3 Orang-orang yang kenal aku pasti tahu kondisiku. Aku capek banget… banget … dengan pikiranku sendiri. Aku mikirin pikiran mereka tentang aku. Mereka Pasti tahu ada yang salah sama aku. Aku paranoid. Mereka bakal tahu tentang kondisiku.4 Aku berusaha menutupi dan berusaha tampil seperti orang yang gak hidup dengan HIV5 tapi gak mungkin karena semakin kamu berusaha berhenti mikirin, semakin sering pikiran itu mengganggu.. Yah.. seperti itulah6
Transkrip pada kolom ini adalah bahan mentah. Jika seluruhnya sudah dibaca, pindah ke kolom kanan
Transkrip pada kolom ini adalah bahan siap olah. Jika seluruhnya sudah diberi tanda, silakan pindah ke langkah kedua
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup180
2. Langkah kedua adalah mengambil transkrip yang sudah berisi unit-unit makna (satuan-satuan makna). Unit-unit makna itu dipisah dengan penomoran sehingga peneliti bisa berfokus pada setiap unit makna. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan setiap unit makna itu dalam bahasa sendiri yang sedekat mungkin dengan bahasa partisipan. Pada tahap ini, kita bisa bertemu dengan ratusan unit makna.
Keterangan:P: Partisipan
Kotak 11.2 Deskripsi untuk Unit Makna
Unit Makna Deskripsi Unit Makna
1. Lebih jauh tentang itu eh … gak tahu gimana yah eh… menurutku sih itu terjadi karena aku, aku, aku gimana yah, aku gak ngerti aja kenapa aku bisa begitu waktu itu
1. P ingin mengungkapkan apa yang terjadi padanya, tetapi tidak tahu apa yang harus dikatakan.
2. saat aku terima diagnosis HIV. Aku gak bisa aja berhenti memikirkannya
2. Sesudah mendapatkan hasil diag nosis, P memikirkan terus hasil diagnosis.
3. dan em … aku harus melewati masa itu dan em rasanya seperti harus belajar lagi mengenal diriku sendiri.
3. P melihat dirinya menjadi berbeda sehingga perlu mengenal kembali diri sendiri.
4. Orang-orang yang kenal aku pasti tahu kondisiku. Aku capek banget… banget … capek dengan pikiranku sendiri. Aku mikirin pikiran mereka tentang aku. Mereka Pasti tahu ada yang salah sama aku. Aku paranoid. Mereka bakal tahu tentang kondisiku.
4. P menjadi paranoid dengan menganggap orang-orang yang dia kenal sedang memikirkan tentang kondisinya dan dia letih sekali dengan pikirannya itu.
5. Aku berusaha menutupi dan berusaha tampil seperti orang yang gak hidup dengan HIV
5. P berusaha menampilkan diri seolah-olah tanpa masalah di depan orang lain.
6. tapi gak mungkin karena semakin kamu berusaha berhenti mikirin, semakin sering pikiran itu mengganggu.. Yah.. seperti itulah.
6. P merasa mustahil melawan pikirannya yang terus sibuk memikirkan hasil diagnosis
BAB XI Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Descriptive Phenomenological Analysis (DPA) 181
3. Setelah selesai dengan unit makna, peneliti kemudian membuat deskripsi psikologis. Bila ada deskripsi unit makna yang berulang dan tidak relevan dengan pertanyaan penelitian, maka kita me nying kirkannya. Beberapa unit makna bisa disatukan bila ada kedekatan makna. Jadi, jumlah deskripsi psikologis bisa lebih sedikit dari jumlah deskripsi unit makna.
Kotak 11.3 Deskripsi Psikologis untuk Deskripsi Unit Makna
Unit Makna Deskripsi Unit Makna Deskripsi Psikologis
1. Lebih jauh tentang itu eh … gak tahu gimana yah eh… menurutku sih itu terjadi karena aku, aku, aku gimana yah, aku gak ngerti aja kenapa aku bisa begitu waktu itu
2. saat aku terima diagnosis HIV. Aku gak bisa aja berhenti memikirkannya
3. dan em … aku harus melewati masa itu dan em rasanya seperti ha rus belajar lagi mengenal diriku sendiri.
4. Orang-orang yang kenal aku pasti tahu kondisiku. Aku capek banget… banget … capek dengan pikiran-ku sendiri. Aku mikirin pikiran mereka tentang aku. Mereka Pasti tahu ada yang salah sama aku. Aku paranoid.
P ingin mengungkapkan apa yang terjadi padanya, tetapi tidak tahu apa yang harus dikatakan.
Sesudah mendapatkan hasil diagnosis, P memikirkan terus hasil diagnosis.
P melihat dirinya menjadi berbeda sehingga perlu mengenal kembali.
P menjadi paranoid dengan menganggap orang-orang yang dia kenal sedang memikirkan tentang kondisinya dan dia letih sekali dengan pikirannya itu.
---- (tidak relevan dan bisa disingkirkan)
P merasakan pikiran yang berulang tentang hasil diagnosis.
P mengalami perubahan persepsi-diri pasca-diagnosis dan berupaya menyesuaikan diri.
P menganggap orang-orang yang dia kenal memikirkan dia yang didiagnosis HIV.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup182
Mereka bakal tahu tentang kondisiku.
5. Aku berusaha menu tupi dan berusaha tam pil seperti orang yang gak hidup dengan HIV
6. tapi gak mungkin karena semakin kamu ber usa-ha berhenti mikirin, se makin sering pikiran itu mengganggu.. Yah.. seperti itulah.
P berusaha menampilkan diri seolah-olah tanpa masalah di depan orang lain.
merasa mustahil melawan pikirannya yang terus sibuk memikirkan hasil diagnosis
5+6: Dalam relasi sosial, P berusaha menutupi kondisinya tapi upaya itu mustahil dipertahankan.
Hasil akhirnya, kolom paling kanan yang bersih dari pernyataan yang berulang, tumpang tindih, dan tidak relevan dengan pertanyaan penelitian.
4. Membuat deskripsi struktural. Deskripsi unit makna dan deskripsi psikologis yang dilakukan peneliti disebut deskripsi tekstural. Deskripsi tekstural ini sudah masuk lebih dalam ke dunia makna di balik transkrip. Tugas kita selanjutnya adalah masuk lebih dalam lagi ke dunia makna di balik deskripsi tekstural itu, yaitu dengan membuat deskripsi struktural. Deskripsi struktural adalah deskripsi yang semakin dekat ke inti pengalaman partisipan.
Kotak 11.4 Deskripsi Struktural untuk Deskripsi Psikologis
Deskripsi Psikologis Deskripsi Struktural
P merasakan pikiran yang berulang tentang hasil diagnosis.
P mengalami perubahan persepsi-diri pasca-diagnosis dan berupaya mende-fini si kan ulang dirinya.
P menganggap orang-orang yang dia ke nal memikirkan dia yang didiagnosis HIV.
Bagi partisipan, pengalaman didiagnosis positif HIV berdampak pada munculnya pikiran yang berulang tentang hasil diag-nosis. Hasil diagnosis itu telah meng-ubah cara partisipan melihat dirinya sen-diri dan dia berusaha menyesuaikan diri dengan dirinya yang baru. Hasil diag-nosis juga memiliki dampak sosial.
BAB XI Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Descriptive Phenomenological Analysis (DPA) 183
(5+6): Dalam relasi sosial, P berusaha menutupi kondisinya tapi upaya itu mustahil dipertahankan.
Partisipan merasakan munculnya pikiran paranoid bahwa orang yang menge nal-nya sedang memikirkan penyakit yang dialaminya. Partisipan berusaha menang-kal pikiran paranoid itu dengan berusaha menunjukkan bahwa tidak ada yang ber ubah dengan dirinya, tetapi upaya itu dianggap mustahil.
5. Mengeksplikasi tema dari deskripsi struktural. Baca deskripsi tekstural di atas dan renungkan dalam keadaan epochē. Sekadar menyegarkan ingatan, penelitian fenomenologis adalah penelitian reflektif dan PFD menekankan epochē itu dalam proses analisis. Dalam keadaan epochē, kita merenungkan (merefleksikan) tema apa yang bisa kita dapatkan dari deskripsi struktural itu. Mari kita tarik deskripsi struktural pada kolom kanan di atas.
Kotak 11.5 Mentransformasikan Deskripsi Struktural Menjadi Tema
Deskripsi struktural
Bagi partisipan dalam penelitian ini, pengalaman didiagnosis positif HIV berdampak pada munculnya pikiran yang berulang tentang hasil diagnosis. Hasil diagnosis itu telah mengubah cara partisipan melihat dirinya sendiri dan dia berusaha menyesuaikan diri dengan dirinya yang baru. Hasil diagnosis juga memiliki dampak sosial. Partisipan merasakan munculnya pikiran paranoid bahwa orang yang mengenalnya sedang memikirkan penyakit yang dialaminya. Partisipan berusaha menangkal pikiran paranoid itu dengan berusaha menunjukkan bahwa tidak ada yang berubah dengan dirinya, tetapi upaya itu dianggap mustahil.
Dengan menjalankan epochē dan variasi imajinatif, peneliti merefleksikan deskripsi struktural di atas. Hasilnya: ......
Tema: Guncangan emosional pasca-diagnosis (Tentu saja tema tidak harus dirumuskan persis seperti ini)
-- Jalankan langkah 1 sampai 5 tersebut untuk masing-masing partisipan --
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup184
Contoh di atas adalah contoh analisis untuk satu partisipan. Kita tidak mungkin menampilkan seluruh transkrip dalam buku ini sehingga kita hanya berlatih dengan potongan transkrip. Dalam analisis riilnya, peneliti akan mengerjakan seluruh transkrip dari seluruh partisipan sampai akhirnya menemukan tema-tema yang lengkap dari setiap partisipan. Kita bisa menyajikan tema seluruh partisipan dalam bentuk tabel rangkuman tema masing-masing partisipan.
Kotak 11.6 Contoh Tabel Penyajian Tema Partisipan
Tema
Partisipan 1 Partisipan 2 Partisipan 3 Partisipan 4
• .......
• .......
• .......
• .......dst
• ......
• ......
• ......
• ......dst
• ......
• ......
• ......
• ......dst
• ......
• ......
• ......
• ......dst
Tema-tema yang muncul di sini telah melewati proses penyaringan. Semakin ketat proses penyaringan, semakin sedikit jumlahnya. Bisa terjadi bahwa deskripsi unit makna yang awalnya berjumlah ratusan berubah menjadi belasan tema saja.
------- Jalankan langkah 6 berikut ini untuk seluruh partisipan -------
6. Membuat sintesis tema. Pada tahap ini, tema-tema dari seluruh partisipan akan diintegrasikan atau disintesiskan menjadi beberapa tema saja. Kita bermaksud menemukan tema-tema esensial atau tema-tema invarian. Jadi, ada proses pengerucutan dari tema-tema individual yang masih cukup banyak menjadi beberapa tema esensial saja. Proses pengerucutan ini butuh variasi imajinatif. Sambil berpegang teguh pada pertanyaan penelitian, kita mengajukan pertanyaan: Tema-tema apa yang menyatukan semua partisipan? Ingat bahwa PFD mencari tema-tema yang umum pada semua partisipan. Tema-tema yang umum itu disebut tema-tema esensial (tema-tema invarian/ konstituen-konstituen invarian) yang semakin
BAB XI Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Descriptive Phenomenological Analysis (DPA) 185
dekat dengan inti. Hasilnya biasanya hanya beberapa tema saja. Banyak dari artikel ilmiah yang saya baca sejauh ini memperlihatkan tema yang berjumlah 3 sampai 6. Kita bisa menyajikan sintesis tema dalam bentuk tabel seperti yang ditunjukkan dalam Kotak 11.7.
Kotak 11.7 Contoh Tabel Penyajian Sintesis Tema
Tema Sintesis
Tema Partisipan 1 Partisipan 2 Partisipan 3 Partisipan 4
• .......
• .......
• .......
• .......dst
• ......
• ......
• ......
• ......dst
• ......
• ......
• ......
• ......dst
• ......
• ......
• ......
• ......dst
• ......
• ......
• ......
Dengan menjalankan epochē dan variasi imajinatif, peneliti merefleksikan seluruh tema di atas dan mencoba menyatukannya. Proses ini bisa dijalankan berkali-kali. Hasilnya adalah munculnya beberapa tema esensial yang yang menyatukan semuanya.
Sintesis yang didapatkan kemudian dideskripsikan. Pada saat men-deskripsikan, perhatian peneliti tidak lagi berfokus pada pengalaman partisipan A, B, C, atau D, tetapi pada pengalaman seluruh partisipan yang dikuatkan dengan potongan transkrip A, B, C, atau D. Jadi, peneliti menarasikan tema-tema hasi sintesis atau integrasi (penggabungan) sambil menguatkan narasinya itu dengan potongan transkrip dari partisipan-partisipan.
Sesudah itu, peneliti membuat deskripsi menyeluruh dengan tidak perlu lagi menyertakan potongan-potongan transkrip. Pada tahap ini, peneliti memberikan narasi tentang partisipan yang berlaku untuk semua partisipan.
--- Langkah 7 berikut ini bersifat fakultatif (boleh ya, boleh tidak) ---
7. Akhirnya, kita sampai pada langkah ketujuh, yaitu menemukan esensi (eidos). Esensi yang ditemukan dirumuskan dalam satu paragraf
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup186
singkat saja. Esensi itu tidak perlu dipaksakan untuk ditemukan karena memang tidak akan muncul dalam keadaan dipaksa. Jika kondisi psikologis dalam keadaan stabil dan tenang, ada kemungkinan intuisi kita bisa bekerja untuk menangkap esensi. Tema esensial adalah tema yang mengikat seluruh pengalaman partisipan. Bila kita menangkap esensi itu, kita bisa mengikutsertakannya dalam laporan. Jika tidak, cukup sampai pada langkah keenam: tema-tema esensial/tema-tema umum/tema-tema pokok/tema-tema utama. Dengan kata lain, pelaporan esensi bersifat fakultatif.
D. Sekilas tentang Esensi dan Intuisi
Husserl mencanangkan fenomenologi yang bertujuan mendeskripsikan esensi atau inti dari pengalaman subjektif. PFD yang setia pada pandangan Husserl mengharapkan peneliti fenomenologis bisa sampai pada esensi itu. Esensi selalu ada di dalam pengalaman partisipan. Hanya saja kita tidak bisa menangkap esensi itu tanpa bantuan intuisi. Padahal, intusi hanya bisa bekerja bila pikiran tenang.
Jika PFD bertujuan menangkap inti dari pengalaman partisipan, maka peneliti yang menggunakan PFD perlu berlatih menenangkan pikiran agar intuisinya bisa bekerja. Caranya sebenarnya sangat sederhana, yaitu fokus dengan santai hanya dan hanya pada transkrip tanpa terpengaruh oleh teori-teori yang sudah bercokol dalam diri, bebas dari keinginan untuk cepat selesai, dan lepas dari macam-macam kekhawatiran. Peneliti cukup berfokus dengan santai pada transkrip dan membiarkan intuisi pelan-pelan memunculkan poin-poin penting dalam transkrip.
Jadi, intuisi dalam PFD berbeda jauh dari apa yang dimengerti orang pada umumnya. Intuisi di sini tidak ada hubungannya dengan firasat atau tebak-tebakan semoga benar. Dengan bekerjanya intuisi, kita tidak lagi menangkap kesan-kesan luar dan dangkal (impressions) yang muncul dari pengalaman partisipan. Dengan menjalankan analisis secara bertahap, peneliti diharapkan mampu menangkap lebih dari sekadar kesan-kesan luar dan dangkal. Pada akhirnya, analisis akan berujung pada kemampuan peneliti meng-intuisi inti (eidos) dari pengalaman partisipan. Amedeo Giorgi
BAB XI Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD): Descriptive Phenomenological Analysis (DPA) 187
(2017:98) menulis tentang peran intuisi itu dalam penelitian fenomenologis deskriptif sebagai berikut.
Teks Asli
When one uses a phenomenological method, phenomenologically speaking, meanings are intuited. Intuition is a term that empiricists seem not to like but phenomenologically it simply means that to which a conscious act is present. So em pi ricists do it all the time. Any object or situation that a person is aware of, pheno menologically he or she is intuiting it.
Transkreasi
Bila Anda menggunakan metode penelitian fenomenologis, maka saat Anda menganalisis data (transkrip) secara fenomenologis, Anda meng-intuisi makna-makna yang muncul dari transkrip. Intuisi adalah istilah yang tidak disukai oleh kaum empi ris (peneliti-peneliti yang akrab dengan metode kuantitatif ). Secara feno meno-logis, intuisi itu sebenarnya hanya berarti sesuatu yang muncul begitu saja dalam kesadaran saat menangkap sesuatu. Jadi, kaum empiris juga selalu menggunakan intuisi. Bila Anda sadar dengan objek atau situasi tertentu, maka secara fenomenologis, Anda mengintuisi objek atau situasi itu.
Saya kira sudah jelas bahwa peneliti yang menggunakan PFD diharapkan bisa menangkap tema-tema (makna-makna) dalam pengalaman partisipan dengan intuisi. Mengintuisi sebenarnya adalah peristiwa alami yang terjadi saat kita memperhatikan sesuatu dengan tenang. Mengintuisi bisa diibaratkan dengan melihat jelas ke dasar telaga yang tenang tanpa riak dan tanpa partikel-partikel kotoran yang mengambang. Mengintuisi adalah melihat dalam keadaan jernih dan tenang.
Dalam psikologi, Carl Gustav Jung adalah tokoh psikologi yang secara eksplisit mengungkapkan bahwa intuisilah yang membuat kita bisa melihat inti dari sesuatu. Untuk lebih jelasnya, saya kutipkan saja apa yang dikatakan Jung (1968:17-18) dalam ceramahnya di London pada tahun 1935.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup188
Teks Asli
When you have an intuitive attitude you usually do not observe the details. You try always to take in the whole of situation, and then suddenly something crops up out of this wholeness.
Transkreasi
Ketika Anda memiliki sikap yang intuitif, Anda umumnya tidak lagi mengamati detail-detail. Anda selalu berusaha menangkap situasi secara menyeluruh (utuh), dan kemudian tiba-tiba saja sesuatu keluar dari situasi yang menyeluruh itu.
Untuk memfasilitasi bekerjanya intuisi, kita lebih dahulu harus mene-nangkan diri dari gejolak emosi, pikiran, dan perasaan. Suasana batin yang tenang adalah prasyarat bekerjanya intuisi. Bila kita meminjam istilah psiko-logi Timur, intuisi bekerja pada orang-orang yang berada dalam suasana medi tatif atau hening. Dalam penelitian fenomenologis, intuisi bisa dilatih dengan menenangkan diri lewat epochē. Prosesnya begini:
• dalam keadaan epochē, kita fokus dan santai saat membaca dan merasakan transkrip secara menyeluruh;
• kitamembacalagiseluruhtranskripdenganfokusdansantaisambilmembatinkan seluruh pernyataan partisipan;
• bila keadaan fokus dan santai itu bisa dijaga, intuisi pelan-pelanmenampilkan poin-poin penting dari seluruh transkrip.;
• poin-poinpentingitulahyangkemudiankitasebutsebagaimakna-makna pokok atau tema-tema pokok.
Begitulah, intuisi tidak bisa dipaksakan untuk bekerja. Kita butuh penga-laman berlatih menenangkan diri agar bisa memiliki intuisi yang tajam. Inilah alasan mengapa saya mengatakan bahwa peneliti yang menggunakan PFD tidak perlu dipaksakan atau memaksakan diri melihat esensi dari seluruh pengalaman partisipan. Kemampuan menangkap tema-tema pokok atau tema-tema utama sudah cukup. Bila toh peneliti bisa menangkap inti atau esensi, maka itu tentu saja sudah lebih dari cukup.
189
BAB XII
Penyusunan Laporan Penelitian
Kita baru saja melewati proses analisis dalam penelitian fenomenologis baik dengan menggunakan IPA maupun dengan menggunakan PFD. Durasi waktu menjalankan analisis sangat ditentukan oleh waktu subjektif masing-masing peneliti. Dalam fenomenologi, kita mengenal dua jenis waktu, yaitu (1) waktu objektif dan (2) waktu subjektif. Saya dan Anda bisa tahu apa itu lima menit, sepuluh menit, atau lima belas menit dengan melihat jam kita masing-masing. Jumlah menit yang diukur dengan alat seperti itu adalah waktu objektif. Pertanyaan berikutnya: Apakah lima menit, sepuluh menit, atau lima belas menit itu adalah waktu yang pendek atau waktu yang lama? Untuk orang yang mengejar kereta atau menunggu ojek di perempatan jalan, lima menit bisa berarti lama sekali. Untuk orang yang menonton film box office kesukaannya di bioskop, waktu lima belas menit begitu cepat berlalu. Nah, itulah waktu subjektif yang sangat tergantung pada kondisi psikologis seseorang.
Jika mahasiswa bertanya, “Lama gak sih Pak melakukan analisis?”, saya biasanya menjawab dengan waktu subjektif, “Cepat kok” sembari mengajaknya larut dalam proses analisis tahap demi tahap sambil melepaskan kekhawatiran dan kecemasan yang melemahkan fokus. Bila mereka bisa menikmati proses analisis, waktu biasanya berlalu tanpa terasa. Analisis data memang butuh suasana tenang dan sedikit meditatif karena kita mau memasuki dunia kehidupan partisipan melalui transkrip. Dalam bahasa Jerman, dunia kehidupan itu disebut Lebenswelt dan dalam bahasa Inggris disebut life-world.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup190
Partisipan mengekspresikan dunia kehidupan (life-world)-nya dalam bahasa sehari-hari. Dalam fenomenologi, bahasa sehari-hari itu disebut bahasa natural. Bila kita berjalan-jalan ke pasar tradisional dan mendengarkan percakapan antara pembeli dan penjual, maka bahasa yang kita dengarkan adalah bahasa natural. Itu juga yang terjadi saat kita mewawancarai partisipan. Partisipan umumnya mengekspresikan pengalamannya dalam bahasa natural. Peneliti fenomenologis ingin melampaui bahasa natural itu. Bila peneliti bisa relaks dan fokus pada bahasa natural itu, maka peneliti pelan-pelan bisa mengakses dunia makna yang tersimpan di balik bahasa natural partisipan kita. Itulah yang diharapkan terjadi dalam analisis data fenomenologis.
Anggaplah, kita sekarang sudah selesai membuat laporan analisis yang lengkap. Dengan kata lain, kita sudah mempunyai temuan-temuan (findings) yang siap untuk dibahas di tengah literatur yang terkait dengan judul penelitian kita. Sambil menyiapkan pembahasan (discussion), ada baiknya bila kita mulai menyiapkan laporan akhir yang akan menjadi materi yang akan dibaca oleh dewan penguji dan peneliti-peneliti lain yang tertarik dengan topik penelitian yang kita jalankan. Inilah yang menjadi fokus kita di bab ini.
A. Judul Penelitian
Mari kita memeriksa lagi judul penelitian kita. Kita masih bisa meng-gantinya dengan bunyi judul yang dirasa lebih menarik perhatian. Kita sudah membicarakan sekilas tentang judul dalam Bab 1 dan kita juga sudah mem bicarakannya secara khusus dalam Bab 3 (Formulasi judul IPA) dan dalam Bab 4 (Formulasi judul PFD). Intinya, ada beragam cara merumuskan judul penelitian. Keberagaman itu dibiarkan saja semakin beragam sejauh sejalan dengan prinsip penelitian fenomenologis. Jika ada keinginan untuk menyeragamkan judul, keinginan itu perlu segera dilepaskan. Peneliti fenomenologis perlu dibiarkan berkreasi dengan rasa bahasanya.
Dalam bab ini, saya ingin kembali menyegarkan pemahaman tentang formulasi judul dengan mengambil fenomena “bermain musik orkestra”. Ini hanya contoh. Mari kita formulasikan fenomena itu menurut versi IPA dan versi PFD (lihat Kotak 12.1).
BAB XII Penyusunan Laporan Penelitian 191
Kotak 12.1 Perbandingan Formulasi Judul IPA dan PFD
IPA PFD
• Interpretativephenomenologicalanaly sis tentang pengalaman ber-main musik orkestra
• Pengalamanbermainmusikorkes-tra: sebuah Interpretative pheno me-no logical analysis
• Interpretativephenomenologicalanalysis tentang bermain musik orkestra
• Maknabermainmusikorkestra:sebuah interpretative pheno meno lo-gical analysis
• Persepsimusisitentangbermainmusik orkestra: sebuah inter-pretative phenomenological analysis
• Interpretativephenomenologicalanalysis tentang dampak bermain musik orkestra
• Saatjiwamembaur: Interpretative phenomenological analysis tentang bermain musik orkestra
• Penelitianfenomenologisdeskriptiftentang pengalaman bermain musik orkestra
• Pengalamanbermainmusikorkes-tra: Penelitian fenomenologis des-krip tif
• Studi(kajian/eksplorasi/investigasi)fenomenologis tentang apa artinya bermain musik orkestra
• Maknabermainmusikorkestra:sebuah penelitian (kajian/eksplo-rasi/investigasi) fenomenologis
• Persepsimusisitentangbermainmusik orkestra
• Saatjiwamembaur:Studi(kajian/eksplorasi/investigasi) fenome nolo-gis tentang pengalaman bermain musik orkestra
• Penelitianeksistensial-fenomeno-logis tentang pengalaman bermain musik orkestra
B. Membuat Judul yang Berdaya Tarik
Dalam penelusuran internet, penelitian fenomenologis yang mengguna-kan IPA lebih mudah ditemukan karena peneliti biasanya menggunakan istilah “interpretative phenomenological analysis” dalam judulnya. Di antara contoh-contoh judul untuk IPA di atas, contoh yang terakhir mungkin terasa aneh. Mengapa tidak menggunakan kata “pengalaman”, “makna”, “arti”, atau “persepsi”? Judul seperti itu sebenarnya bagus dan menarik perhatian pembaca dan biasanya dibuat sesudah menganalisis seluruh partisipan. Dari
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup192
tema-tema yang sudah ditemukan, peneliti kemudian merasa bahwa ada “tema pokok” yang menyolok ditemui pada seluruh partisipan. Tema pokok yang menyolok itulah yang kita tampilkan. Bunyi judul bisa juga diambil dari pernyataan satu partisipan, tetapi pernyataan itu cukup representatif untuk mewakili pengalaman partisipan-partisipan yang lain. Meski rumusan judul seperti ini menarik, peneliti tidak perlu memaksakan diri bila memang peneliti belum merasakan sesuatu yang menyolok untuk ditampilkan dari semua partisipan. Sekarang, perhatikan lagi judul penelitian IPA berikut.
Teks Asli
‘Me and my bump’: an interpretative pheno menological analysis of the expe-
riences of pregnancy for vulnerable women.
Birtwell, Hammond, Puckering.
Abstract
Eight pregnant women, considered to be ‘vulnerable’ due to exposure to a number of underlying risk factors, participated in semi-structured interviews regarding their experiences of pregnancy and of Mellow Bumps, a 6-week targeted antenatal intervention. Interview transcripts were explored using interpretative phenomenological analysis. The analysis revealed five superordinate themes: pregnancy as a time of reflection; the body being taken over; pregnancy as an emotional rollercoaster; relationships as important; separating identities. Pre- and post-natal attachment theories were found to be useful in interpreting the data. Findings suggest that pregnancy may be ‘normalising’ and provide an important opportunity for building
Transkreasi
“Aku dan Jendulanku”: IPA tentang pengalaman kehamilan pada wanita-wanita rentan
Delapan wanita hamil yang diang gap “rentan” berpartisipasi dalam wawan-cara semi terstruktur untuk memberi informasi tentang pengalaman kehamilan mereka dan Mellow Bumps, yaitu intervensi sebelum persalinan (antenatal) yang berlangsung selama enam minggu untuk mengurangi level stres dari calon ibu. Transkrip-transkrip wawancara dieksplorasi meng gunakan interpretative pheno-me no logical analysis (IPA). Analisis menunjukkan lima tema superordinat, yaitu (1) kehamilan sebagai masa refleksi; (2) badan yang diambil alih; (3) kehamilan sebagai rollercoaster emosional; (4) hubungan sebagai hal yang penting; dan (5) identitas-identitas yang terpencar. Teori-teori kelekatan pra- dan pascanatal bermanfaat dalam menginterpretasikan
BAB XII Penyusunan Laporan Penelitian 193
more positive representations of the self. Findings also provide clinical support for the assertion that the attachment relationship begins before birth. The Mellow Bumps intervention was uniformly seen as helpful. It appeared to nurture prenatal attachment relationships, playing a potentially protective role, by helping to establish the foundations for secure mother-infant relationships in the future. Meeting similar women and engaging in ordinary, supportive conversation during Mellow Bumps seemed to reduce feelings of isolation and stigma. Implications for clinical practice are considered.
data. Temuan-temuan menunjukkan bahwa kehamilan bisa saja ‘menjadi normal’ dan memberikan kesempatan penting untuk membangun gambaran diri yang lebih positif. Temuan-temuan juga memberikan dukungan klinis untuk pernyataan bahwa hubungan kemelekatan mulai sebelum kelahiran. Intervensi Mellow Bumps dianggap bermanfaat oleh semua partisipan. Intervensi tampaknya menguatkan hubungan-hubungan kemelekatan pranatal, memainkan peran yang secara potensial protektif, dengan membantu membangun fondasi untuk hubungan ibu-anak yang nyaman di masa depan. Bertemu dengan wanita-wanita serupa dan terlibat dalam obrolan biasa dan suportif selama Mellow Bumps tampaknya bisa mengurangi perasaan isolasi dan stigma. Implikasi-implikasi dari praktik klinis dibahas dalam penelitian ini.
Peneliti fenomenologis deskriptif juga bebas berkreasi dalam merumuskan judul penelitian sejauh berbasis pada prinsip-prinsip fenomenologis. Di antara judul-judul di atas, judul yang terakhir sedikit melenceng. Sejauh ini, kita belum pernah membicarakan formulasi judul dengan menggunakan “eksistensial”. Sebenarnya itu juga hanya variasi judul dalam PFD. Untuk sementara, cukup diingat bahwa ada istilah “eksistensial-fenomenologis”. Istilah “eksistensial” itu sendiri penting untuk diketahui oleh peneliti fenomenologis deskriptif sehingga saya perlu membicarakannya khusus secara terpisah di Bab 13.
Masih ada cara lain untuk merumuskan judul PFD, yaitu dengan kalimat tanya yang memberi gambaran sekilas tentang tema yang menonjol pada partisipan. Berikut ini adalah contoh judul PFD yang memunculkan
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup194
kebutuhan partisipan untuk didengarkan dan dimengerti dalam kalimat tanya.
Teks Asli
Is anybody listening? A phenomenological study of pain in hospitalized persons with
AIDS.
Newshan G
Abstract
Pain is a common problem among hospi-talized persons with AIDS (PWAs), yet it has not been well studied. The pur pose of this study was to understand, using the phenomenological method, the expe-rience of pain in hospitalized PWAs. Multiple sources of data, including inter views with 11 hospitalized PWAs, literature, poetry, and film, were used to investigate the phenomenon. Five broad themes emerged: knowing pain, battling pain, having AIDS, pain’s influence, and being a drug user. Multiple barriers to effective pain management were identified. Although there were commonalities in the experience of pain in chemically dependent and nonchemically dependent PWAs, unique challenges for the chemically dependent PWAs were identified. The findings indicate the importance of listening to and believing reports of pain. In addition, the findings underscore the delicate balance that exists between pain relief and relapse in PWAs with a history of chemical dependency.
Transkreasi
Adakah yang mendengarkanku? Studi fenomenologis tentang rasa sakit pada
penderita AIDS yang dirawat inap.
Rasa sakit adalah masalah yang umum di antara orang-orang yang dirawat inap karena menderita AIDS (Dalam bahasa Inggris dikenal dengan singkatan PWAs [people with Aids/orang-orang dengan Aids]). Meski demi kian, belum ada kajian yang memadai tentang rasa sakit itu. Tujuan dari penelitian ini adalah meng-guna kan metode fenomenologis untuk memahami pengalaman akan rasa sakit oleh PWAs. Data yang multisumber dalam penelitian ini meliputi wawancara dengan 11 pen-derita AIDS yang dirawat inap. Pene liti juga menggunakan literatur, puisi, dan film. Lima tema besar yang muncul adalah: mengenai rasa sakit, bertarung melawan rasa sakit, mengidap AIDs, pengaruh rasa sakit, dan pengguna obat/berbagai tantangan untuk memanajemen rasa sakit diidentifikasi. Meskipun ada kemiripan dalam pengalaman akan rasa sakit pada penderita PWAs baik yang tergantung pada obat kimiawi dan obat nonkimiawi, peneliti mene mu kan adanya tantangan-tan tangan unik pada
BAB XII Penyusunan Laporan Penelitian 195
PWAs yang tergantung pada obat kimiawi. Temuan-temuan menunjuk-kan pentingnya men dengar kan dan memercayai laporan mereka akan rasa sakit. Temuan-temuan juga melihat pentingnya keseimbangan antara kelegaan rasa sakit dan kekambuhan pada PWAs yang punya sejarah ketergantungan pada obat kimiawi.
Memang ada kebebasan dalam merumuskan judul, tetapi peneliti sebaik-nya memberi kesan “wow” atau menampilkan judul yang punya daya tarik atau daya pikat. Dalam kelas, saya biasanya meminta seorang mahasiswa membacakan bunyi judul penelitiannya sambil memperhatikan reaksi teman-temannya segera sesudah judul dibunyikan. Judul penelitian yang baik bisa dengan cepat menarik perhatian pembaca sekaligus memberi informasi tentang proyek penelitian yang ingin dijalankan.
C. Penulisan Abstrak
Abstrak adalah gambaran singkat dan jelas tentang proyek penelitian yang dijalankan. Bisa dikatakan bahwa abstrak adalah rangkuman pendek dari proses penelitian yang sudah dijalankan. Abstrak juga perlu dirumuskan dengan baik agar punya daya tarik yang mengudang pembaca untuk tahu lebih jauh tentang penelitian yang sudah dilakukan. Di bagian “Judul Penelitian”, kita baru saja bertemu dengan dua contoh abstrak. Me mang tidak ada keseragaman dalam cara penulisan abstrak, tetapi poin-poin berikut diharapkan bisa ditemukan dalam abstrak Anda.
1. Persoalan yang menjadi perhatian 2. Gambaran umum tentang penelitian3. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian4. Gambaran tentang sampling dan sampel5. Gambaran singkat tentang pengumpulan data dan metode analisis
data6. Rangkuman untuk temuan
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup196
7. Signifikansi dan relevansi penelitian bagi penelitan-penelitian lain
Kotak 12.2 Contoh Abstrak dan Bagian-bagiannya
Abstrak Bagian Abstrak
Penelitian tentang hubungan guru dan murid dalam tradisi Sufi masih jarang ditemukan. Padahal, relasi guru-murid adalah penentu utama bagi seorang pengikut sufisme untuk memahami lebih dalam tentang hubungan pribadinya dengan Allah.1 Penelitian ini mengisi kekurangan itu dengan mengeksplorasi peran syekh dalam memandu murid di jalan sufi.2 Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana syekh memaknai pengalaman pribadinya sebagai pembimbing bagi murid di jalan sufi.3 Sampling purposif digunakan untuk merekrut tiga syekh dari tarekat Naqshbaadi.4 Wawancara dijalankan secara semi-terstruktur. Transkrip wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretative phenomenological analysis.5 Ada empat tema superordinat yang ditemukan: (1) Allah sebagai satelit dalam membimbing, (2) rasa syukur menjadi murid seorang syekh, (3) membimbing sebagai tanggung jawab besar, dan (4) problem dalam membimbing murid.6 Lewat penelitian ini, partisipan menyampaikan pengalaman pribadinya dalam membimbing murid di jalan Sufi.7 Temuan dalam penelitian ini bisa menjadi masukan bagi psikologi transpersonal dalam memahami peran guru sebagai unsur penting dalam tradisi sufi.8
1. Persoalan yang menjadi perhatian peneliti.
2. Gambaran umum tentang penelitian
3. Tujuan penelitian untuk paham pengalaman
4. Sampling dan sampel
5. Metode pengumpulan data dan metode analisis data.
6. Temuan (hasil analisi data)
7. Rangkuman
8. Pentingnya riset ini dan kaitan dengan riset lain.
D. Latar Belakang (Introduction/Background)
Latar belakang dalam penulisan karya ilmiah adalah pengantar tentang proyek penelitian yang dijalankan. Latar belakang umumnya memberi gambaran tentang masalah yang menjadi perhatian peneliti. Jadi, ada masalah yang dilihat dari perspektif keilmuan si peneliti. Berpangkal dari masalah itu, peneliti lalu mencari tahu sejauh mana literatur dalam keilmuannya berbicara tentang persoalan itu. Akhirnya, peneliti mengajukan pertanyaan yang ingin dijawab lewat penelitiannya. Untuk mengetahui apakah latar
BAB XII Penyusunan Laporan Penelitian 197
belakang penelitian sudah dikemukakan dengan baik, poin-poin berikut bisa menjadi panduan.
Kotak 12.3 Pengecekan Isi Latar Belakang
No. Pernyataan Cek
1. Saya sudah mengemukakan proyek penelitian yang saya jalankan. √
2. Saya sudah menggunakan literatur secara singkat dan kritis untuk memberi gambaran tentang kondisi saat ini dalam bidang atau area penelitian saya.
√
3. Saya sudah mengemukakan masalah tertentu yang saya rasa kurang mendapat perhatian atau bahkan belum mendapat perhatian sehingga menjadi perhatian saya.
√
4. Saya sudah mengemukakan mengapa saya menggunakan PFD atau IPA dan juga sudah memberi alasan teoretis mengapa saya mengggunakan penelitian fenomenologis deskriptif atau interpretatif.
√
5. Saya sudah menunjukkan dengan jelas bahwa penelitian fenomenologis memang sesuai dengan kebutuhan saya dalam menjawab persoalan dan sejalan dengan tujuan penelitian saya. Singkatnya, saya sudah menunjukkan mengapa saya memilih fenomenologis-interpretatif/fenomenologis-deskriptif di antara beberapa model penelitan kualitatif.
√
6. Saya sudah menutup latar belakang penelitian saya dengan mengajukan pertanyaan penelitian.
√
E. Metode (Method)
Istilah metode berasal dari kata Yunani metodhos yang berarti jalan atau cara. Dengan menggunakan metode, kita sebenarnya memilih jalan yang akan kita tempuh untuk sampai pada tujuan. Peneliti perlu mempertimbangkan metode yang sesuai bagi tujuan dan pertanyaan penelitiannya tanpa ter-jerumus ke dalam klaim bahwa metode tertentu adalah metode yang paling benar dan paling baik. Peneliti yang mengklaim bahwa metode tertentu adalah metode yang paling benar tenggelam dalam apa yang bisa disebut sebagai metodolatri atau metodisme, yaitu pemujaan pada metode sampai lupa bahwa metode itu hanya jalan atau cara yang bisa cocok bisa juga tidak cocok, bisa relevan bisa juga tidak relevan, bisa tajam bisa juga tumpul.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup198
Keberagaman metode harus dihargai sejauh bisa dipertanggungjawabkan sebagai jalan/cara yang bisa mengantar sampai pada tujuan.
Dalam laporan penelitian fenomenologis kita, bagian metode diharapkan bisa menunjukkan dengan jelas bahwa peneliti menempuh jalan atau cara yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian umumnya dimunculkan di Bab III. Bagian metode kita akan memberi informasi kepada pembaca tentang poin-poin berikut.
1. Metode fenomenologis yang digunakan
Kita bisa membuka segmen metode penelitian dengan memberi penjelasan singkat tentang penelitian kualitatif yang kemudian meng-a rah pada penelitian fenomenologis sebagai salah satu pendekatan kualitatif yang akan digunakan. Peneliti kemudian lebih tajam lagi mengarah pada versi penelitian fenomenologis yang digunakan (IPA atau PFD). Jelaskan secara singkat apa tujuan dan manfaat dari IPA atau PFD. Berikan juga penjelasan singkat tentang mengapa pilihan dijatuhkan pada IPA atau PFD.
2. Sampling dan proses rekrutmen partisipan
Umumnya, penelitian kualitatif menggunakan sampling purposif. Peneliti juga memberi gambaran tentang bagaimana peneliti mene-mukan atau merekrut patisipan. Seandainya saja ada orang-orang yang sudah membantu peneliti sehingga bisa bertemu dengan partisipan, peneliti perlu juga memberi gambaran tentang mereka tanpa menyebutkan nama.
3. Gambaran demografis partisipan
Peneliti biasanya menyajikan informasi demografis dalam bentuk tabel. Gambaran demografis ini bertujuan memperjelas identitas partisipan, seperti usia, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Da lam tabel itu, selalu jaga kerahasiaan identitas partisipan dengan menya-markan nama.
4. Pengumpulan data
Peneliti menjelaskan proses pengumpulan data mulai dari pengem-bangan pertanyaan penelitian, metode wawancara yang digunakan, perekaman data, atau transkripsi data.
BAB XII Penyusunan Laporan Penelitian 199
5. Tahap-tahap analisis
Dalam IPA tahap-tahap analisis itu antara lain:a. membaca transkrip berkali-kali,b. melakukan pencatatan inisial untuk transkrip dengan memberi-
kan komentar eksploratoris,c. memunculkan tema emergen,d. memunculkan tema superordinat masing-masing perserta,e. memunculkan tema superordinat antarpartisipan,f. mendeskripsikan tema-tema superordinat antarpartisipan yang
ditemukan.
Sedangkan dalam metode fenomenologis deskriptif yang menggu-nakan DPA, tahap-tahap analisisnya antara lain:a. berkomitmen menjalankan epochē,b. membaca transkrip berkali-kali dan memunculkan unit-unit
makna,c. membuat deskripsi psikologis untuk unit-unit makna,d. membuat deskripsi struktural,e. mengeksplikasi tema dari deskripsi struktural,f. membuat sintesis tema, g. menemukan esensi dari pengalaman seluruh partisipan (fakultatif ).
6. Validitas penelitian
Peneliti kualitatif, khususnya peneliti fenomenologis, perlu menun-jukkan bagaimana validitas ditegakkan. Tapi bukanlah validitas adalah istilah khusus penelitian kuantitatif ? Istilah “validitas” tidak perlu dikurung dan dieksklusifkan seperti itu. Dalam bahasa Latin, validus berarti kuat atau efektif. Tapi kalau seandainya istilah “validitas” masih juga mengganjal, istilah “verifikasi” boleh digunakan. Istilah “verifikasi” itu sendiri juga berasal dari bahasa latin “verus” yang berarti benar. Artinya, peneliti berkomitmen menempuh proses penelitian yang benar. Silakan memilih: validitas atau verifikasi. Yang jelas, istilah “validitas” dan “verifikasi” kita gunakan sebagai upaya menunjukkan bahwa penelitian sudah berjalan sesuai dengan tuntutan-tuntutan dalam penelitian kualitatif pada umumnya, atau penelitian fenomenologis pada khususnya (lihat Kotak 12.4).
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup200
7. Penerapan kode etik
Peneliti menjalankan risetnya dengan memperhatikan etika. Etika di sini berarti panduan tentang apa itu baik dan buruk yang disepakati dalam organisasi yang menaungi peneliti. Untuk peneliti psikologi di Indonesia, misalnya, penelitian dijalankan dengan menerapkan etika penelitian yang diberlakukan dalam organisasi yang bernama Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Di sini, saya hanya perlu menampilkan empat poin penting yang perlu mendapat perhatian peneliti fenomenologis, yaitu (1) penyediaan lembar informasi (infor mation sheet) yang berisi informasi tentang penelitian kepada partisipaan, (2) penyediaan lembar persetujuan (consent form/informed consent) yang dibaca dan ditandatangani sebelum wawancara, (3) komitmen peneliti untuk menjaga kerahasiaan dengan menyamarkan identitas partisipan, dan (4) refleksi peneliti tentang dampak atau konsekuensi yang merugikan dari penelitiannya baik bagi kehidupan pribadi partisipan (misalnya, pengalaman traumatis yang masih dalam proses pemulihan) maupun kondisi sosial (misalnya, pengalaman yang sensitif menimbukan gejolak dalam masyarakat).
8. Refleksi peneliti
Judul fenomenologis tidak datang tiba-tiba, tetapi muncul dari rasa tertarik dan suka pada suatu fenomena (pengalaman) tertentu. Saya ingin menyegarkan lagi ingatan tentang pentingnya epochē. Kita harus berani melihat kecenderungan-kecenderungan dalam diri kita sendiri yang bisa menghambat kita dalam melihat pengalaman orang lain apa adanya. Refleksi diri adalah salah satu upaya peneliti untuk melihat ke dalam diri sendiri sambil menetralkan diri dari potensi mengotori pengalaman partisipan dengan pengalaman pribadi. Refleksi berasal dari kata Latin reflectere yang berarti mem-bungkukkan badan, mirip dengan cara orang Jepang memberi hormat kepada orang lain. Dalam refleksi diri, peneliti dengan rendah hati mengungkapkan pandangan-pandangan, perasaan-perasaan, praduga-praduga, atau angggapan-anggapan yang terkait dengan judul penelitian. Ini salah satu cara untuk jujur dengan diri sendiri sekaligus menguatkan epochē.
BAB XII Penyusunan Laporan Penelitian 201
Kotak 12.4 Validitas (Kualitas Penelitian) dalam Penelitian Fenomenologis
Edmund Husserl mencita-citakan fenomenologi sebagai metode penelitian untuk pengalaman subjektif yang dijalankan secara ketat (rigorous) atau dalam istilah yang lebih umum dibunyikan "ilmiah (scientific)". Peneliti fenomenologis perlu menunjukkan bahwa penelitiannya sudah berjalan secara ketat/ilmiah dengan menunjukkan validitas (validity) atau upaya verifikasi (verification) atau keterpercayaan (trustworthiness). Silakan menggunakan salah satu dari tiga istilah itu yang Anda anggap sesuai. Poin intinya adalah: Apa yang membuat penelitian kualitatif berkualitas? Salah satu referensi yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah keterpercayaan yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985) yang terdiri dari empat kriteria kualitas (quality criteria), yaitu (1) kredibilitas, (2) transferabilitas, (3) dependabilitas, dan (4) konfirmabilitas. Tidak sulit menemukan empat kriteria ini dalam buku-buku metodologi penelitian kualitatif dan saya tidak perlu membicarakannya di sini. Cukup diingat bahwa di dalam setiap kriteria itu, ada poin-poin yang perlu dijalankan oleh peneliti. Tidak semua poin itu harus dijalankan. Peneliti secara selektif menentukan poin-poin yang dibutuhkan oleh pendekatan kualitatif dijalankan (misalnya, pendekatan naratif, grounded theory, etnografis, studi kasus, analisis diskursus, atau fenomenologis).
Untuk penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, empat kualitas esensial yang dikemukakan Lucy Yardley (2007) tampaknya relevan digunakan untuk penelitian fenomenologis. Keempat kualitas itu adalah sebagai berikut.
1. Sensitivitas terhadap konteks (sensitivity to context). Peneliti perlu menunjukkan bahwa dia sensitif atau sudah sungguh-sungguh memperhatikan konteks kehidupan partisipan.
2. Komitmen dan keilmiahan (commitment and rigour). Komitmen di sini terkait dengan keseriusan dan keterlibatan penuh dalam menjalankan penelitian; sementara rigour berarti proses pengumpulan data dan analisis dijalankan dengan tahapan yang utuh;
3. Transparansi dan koherensi (transparency and coherence). Transparansi berarti peneliti perlu terbuka dengan metode dan alur analisisnya; sementara koherensi berarti kesesuaian pertanyaan penelitian dengan filsafat, metode, dan alur analisis yang digunakan.
4. Dampak dan kebermanfaatan (impact and importance). Ini berarti penelitian punya dampak teoretis, praktis, dan sosiokultural.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup202
Berikut ini daftar pernyataan yang kami kembangkan dari empat kualitas yang dijabarkan oleh Yardley (2000). Setiap pernyataan sudah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian fenomenologis.
NO KUALITAS ESENSIAL Cek
1. Sensitivitas pada Konteks
Saya menggunakan literatur yang relevan dengan pertanyaan penelitian saya.
√
Saya mendapatkan data-data empiris yang berbasis pada pengalaman langsung dari partisipan.
√
Saya memperhatikan konteks sosiokultural untuk penelitian saya. √
Saya memperhatikan perspektif partisipan dalam dunia pengalamannya.
√
Saya mempertimbangkan masalah-masalah etis dalam penelitian saya.
√
2. Komitmen dan Rigor
Saya memahami metode fenomenologis yang saya gunakan. √
Saya mendapatkan informasi yang dalam dari partisipan. √
Saya menganalisis data secara detail. √
3. Transparansi dan koherensi
Interpretasi/deskripsi saya dan argumentasi saya jelas dan transparan.
√
Metode yang saya gunakan jelas transparan. √
Penyajian data saya jelas dan transparan. √
Metode fenomenologis yang saya gunakan sejalan dengan perspektif teoretis yang mendasarinya.
√
Saya manjalankan refleksivitas dalam penelitian saya. √
4. Dampak dan Kebermanfaatan
Temuan saya memberi sumbangan pemahaman teoretis. √
Penelitian saya punya dampak secara sosiokultural. √
Penelitian saya punya dampak praktis untuk bidang ilmu yang saya tekuni.
√
BAB XII Penyusunan Laporan Penelitian 203
F. Hasil Analisis Data
Bagian ini umumnya ditemui dalam Bab 4 laporan penelitian skripsi, tesis, atau disertasi. Hasil analisis data pada dasarnya berisi komunikasi yang mengalir antara peneliti dan pembaca mengenai tema-tema pokok atau tema-tema utama yang ditemukan dalam penelitian. Dalam IPA, tema-tema pokok/utama itu disebut tema-tema superordinat; sementara dalam penelitian fenomenologis deskriptif, tema-tema pokok itu umumnya disebut tema-tema invarian (struktur-struktur invarian/konstituen-konstituen inva-rian). Ingat bahwa tema-tema pokok yang kita laporkan keluar dari dunia pengalaman partisipan. Laporan kita hanyalah interpretasi (dalam IPA) atau deskripsi terhadap pengalaman partisipan (dalam PFD). Lewat wawancara, kita bertemu langsung dengan orang-orang yang mengalami langsung suatu fenomena (peristiwa mental) dan mendengarkan pengalaman mereka. Hasil dari pertemuan langsung itu kemudian dianalisis. Setelah melewati tahapan analisis, kita pelan-pelan menjadi paham. Hasil penelitian adalah memberitahukan pemahaman kita sebagai peneliti tentang pengalaman partisipan.
• Dalam IPA, hasil analisis berupa pelaporan tema-tema pokok yang disebut tema-tema superordinat (untuk subjek/partisipan tunggal) atau tema-tema superordinat lintas partisipan (untuk beberapa subjek/partisipan). Tema-tema superordinat itu didapatkan dari tema-tema emergen. Dalam IPA, terjadi pergerakan dari tema emergen menuju tema superordinat.
• Dalam PFD, hasil analisis berisi laporan tema-tema, sintesis tema-tema, dan esensi (struktur umum). Esensi adalah inti yang didapatkan setelah menyatukan atau menyintesiskan tema-tema yang sebelumnya bervariasi pada masing-masing subjek/partisipan. Dalam PFD, terjadi pergerakan dari deskripsi pengalaman masing-masing partisipan menuju deskripsi yang menyatukan pengalaman seluruh partisipan.
G. Pembahasan (Discussion)
Kita bisa mengibaratkan temuan atau hasil analisis dengan perahu yang akan dimasukkan ke dalam telaga ilmu pengetahuan, khususnya ilmu
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup204
pengetahuan yang terkait dengan bidang keilmuan peneliti. Dalam telaga ilmu pengetahuan itu, ada banyak perahu lain yang sudah mengapung. Perahu-perahu yang lain adalah literatur-literatur yang ada dalam psikologi. Saat peneliti membahas temuan-temuannya, ia memasukkan perahunya ke dalam telaga dan melihat seperti apa perahu itu di antara perahu-perahu yang lain. Itulah yang terjadi dalam pembahasan. Poin-poin dalam Kotak 12.4 dapat menjadi panduan peneliti dalam membahas hasil analisisnya.
Kotak 12.5 Pengecekan Isi Pembahasan
No. Deskripsi Cek
1. Peneliti mengemukakan kemiripan dan perbedaan antara hasil analisis datanya dan literatur yang ada. Beberapa dari literatur itu bisa ditemukan di bagian pengantar (umumnya diposisikan sebagai Bab 1: Latar Belakang) dan reviu pustaka (umumnya diposisikan sebagai Bab 2: Tinjauan Pustaka).
√
2. Peneliti membicarakan literatur secara selektif saja. Ada begitu banyak literatur yang bisa diakses baik di perpustakaan universitas, perpustakaan umum, atau perpustakaan digital. Peneliti perlu selektif melihat literatur-literatur yang terkait erat dengan temuan-temuannya.
√
3. Peneliti menampilkan keunggulan dan kekurangan dari penelitiannya. √
4. Peneliti mengemukakan kebermanfaatan praktis dari penelitian yang digunakan bagi bidang-bidang tertentu dalam psikologi dalam disiplin ilmu kemanusiaan lain yang sedang digeluti.
√
5. Peneliti memberi saran untuk penelitian di masa depan. √
H. Kesimpulan
Dalam bagian kesimpulan, peneliti memberi penjelasan yang singkat, padat, dan jelas tentang proses penelitian yang dia jalankan. Poin-poin dalam Kotak 12.5 bisa menjadi panduan dalam menyusun kesimpulan.
BAB XII Penyusunan Laporan Penelitian 205
Kotak 12.6 Pengecekan Isi Kesimpulan
No. Deskripsi Cek
1. Peneliti mulai bercerita secara singkat tentang ketertarikannya pada fenomena yang kemudian menjadi judul penelitiannya. Peneliti boleh menampilkan peristiwa atau literatur yang mendorongnya melakukan penelitian fenomenologis.
√
2. Peneliti mengemukakan secara singkat tentang kelangkaan atau belum adanya riset kualitatif tentang fenomena yang menjadi perhatiannya.
√
3. Peneliti menceritakan secara singkat bagaimana dia sampai pada keputusan menjalankan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, khususnya IPA atau PFD.
√
4. Peneliti memberi penjelasan singkat tentang tujuan penelitian dan bagaimana tujuan itu sejalan dengan tujuan penelitian fenomenologis yang digunakan, khsususnya IPA atau PFD.
√
5. Peneliti bercerita secara singkat tentang proses rekrutmen partisipan, jumlah partisipan, dan proses pengumpulan data.
√
6. Peneliti menyampaikan secara singkat tema-tema superordinat (untuk IPA) atau tema-tema invarian (untuk PFD) yang ditemukan.
√
7. Peneliti menginformasikan secara singkat relevansi dan manfaat dari temuan-temuannya baik bagi psikologi sebagai ilmu maupun bagi praktisi psikologi sebagai pribadi-pribadi yang menggunakan psikologi dalam profesi mereka.
√
Dengan sengaja, saya berkali-kali menggunakan kata “singkat” untuk menekankan perlunya menghindari kesimpulan yang terlalu panjang. Ke-sim pulan atau konklusi berasal dari kata Latin “concludere” yang bisa ber-arti “menutup” dan bisa juga berarti “menampung”. Dengan membuat kesimpulan, kita diharapkan membuat pernyataan penutup yang mewadahi aktivitas-aktivitas pokok kita selama penelitian.
I. Format Susunan Laporan Penelitian
Format laporan penelitian yang akan kita bicarakan di sini adalah format laporan penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi. Susunan umum tentu saja bisa berbeda antardisplin ilmu atau antarfakultas sehingga jumlah
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup206
bab dalam suatu skripsi, tesis, atau disertasi bisa bervariasi. Berikut ini adalah salah satu alur penyajian laporan yang bisa digunakan.
Sampul
Halaman Judul
Halaman pengesahan
Ucapan terima kasih (untuk orang-orang yang memang dirasakan kasihnya)
Daftar isi
Daftar tabel
Daftar gambar (kalau ada)
Daftar bagan dan skema (kalau ada)
Abstrak
Bab 1: Latar Belakang
Bab 2: Reviu Literatur
Bab 3: Metode Penelitian
• Sampling+gambarandemografispartisipan• Prosesanalisis• Validitas/verifikasi• Refleksipeneliti
Bab 4: Hasil Analisis (Narasikan temuan berdasarkan hasil analisis peneliti baik dengan IPA maupun dengan PFD. Detail tahapan analisis dari trans-krip orisinal sampai penemuan tema pokok dimasukkan ke lampiran)
Bab 5: Pembahasan dan Kesimpulan (Dalam pembahasan, posisikan temuan di tengah literatur yang terkait dengan judul penelitian)
Bab 6: Keterbatasan dan Saran
Daftar pustaka
Lampiran. (Umumnya berisi dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang diperlu-kan untuk pengumpulan data dan analisis data. Isi lampiran bervariasi sehingga perlu disesuaikan dengan persyaratan lembaga pendidikan tempat
BAB XII Penyusunan Laporan Penelitian 207
Anda melakukan riset. Di Inggris, misalnya, harus ada surat persetujuan komisi etik).
• Lampiran 1: Lembar informasi (information sheet)• Lampiran 2: Lembar persetujuan (consent form/informed consent
tanpa identitas partisipan untuk menegakkan kode etik riset)• Lampiran 3: Contoh bagian Trankskrip (beberapa halaman awal
saja)• Lampiran 4: Contoh penemuan tema (dalam bentuk tabel)
(beberapa halaman awal saja)• Lampiran 5:
• Tabelindukdaritemasuperordinat(untuksubjektunggal)atau tema antarpartisipan (untuk subjek jamak) (untuk IPA)
• Tabel pembentukan tema-tema esensial atau konstituen-konstituen esensial (untuk PFD)
• Lampiran 6: Tabel tema berulang (untuk IPA)• Lampiran 7: Surat izin penelitian dari kampus• Lampiran 8: Jadwal Penelitian
209
BAB XIII
Penelitian Eksistensial-fenomenologis?
Dalam Bab XIII ini, kita akan membicarakan satu topik penting yang dengan sangaja saya tunda untuk dibicarakan di bab-bab sebelumnya. Dalam Bab XII yang baru saja kita lewati, saya juga memberi satu contoh judul penelitian yang berbunyi: “Penelitian eksistensial-fenomenologis tentang pengalaman bermain musik orkestra”.
Bila Anda melakukan penelusuran di internet via Google, sangat mudah menemukan judul-judul penelitian yang menggunakan kata “eksistensial-fenomenologis”. Dalam Kotak 13.1, Anda bisa melihat hasil penelusuran yang saya lakukan pada tanggal 18 Mei 2017.
Kotak 13.1 Penelusuran Online Judul Penelitian Eksistensial-Fenomenologis
Sumber: www.google.com
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup210
Dalam bab 10, kita membicarakan sekilas tentang Amedeo Giorgi sebagai peletak dasar penelitian fenomenologis deskriptif. Saat melakukan penelusuran internet, saya bertemu dengan satu tulisan dari seorang psikolog dan peneliti Italia yang mengulas PFD Amedeo Giorgi dan mencoba mengembangkan model analisis berbasis fenomenologi deskriptif. Berikut abstrak dari artikel itu.
Teks Asli
Introduction to Giorgi’s Existential Phenomenological Research Method
Alberto De Castro
Abstract
This article offers a brief introduction to the theoretical bases on which Amedeo Giorgi supports his research work with a phenomenological existential approach. In the same way, it shows the different steps followed by that author in order to analyze the collected data in a research.
Transkreasi
Artikel ini memberikan pengantar sing kat tentang dasar-dasar teoretis yang menjadi tumpuan Amedeo Giorgi dalam mengembangkan pene-litian dengan pendekatan eksistensial fenomenologis. Dalam artikel ini, penulis menawarkan langkah-lang-kah lain yang bisa digunakan meng-anali sis data. Pengembangan tahapan analisis data ini juga masih berdasar pada pendekatan eksistensial-fenomenologis.
Jika, penelitian fenomenologis yang dikemukakan Giorgi adalah pene-litian fenomenologis deskriptif (PFD), mengapa penulis artikel di atas menyebutnya esksistensial-fenomenologis? Memang sepanjang buku ini, kita belum berbicara apa pun tentang apa itu “eksistensial” dan mengapa istilah itu bisa dikaitkan dengan istilah “fenomenologis”. Sejak awal menulis buku ini, saya berniat menghindari pembicaraan yang terlalu filosofis. Untuk saat ini, kita perlu menjadi lebih filosofis. Kita tidak bisa menghindari pembicaraan filsafat eksistensial (eksistensialisme) bila kita ingin memahami apa itu “eksistensial-fenomenologis”.
Pengembangan PFD sulit dilepaskan dari sekelompok peneliti yang mengembangakan penelitian eksistensial-fenomenologis di Universitas Duquesne (Baca: du-kene). Ada beberapa tokoh psikologi yang mengem-bang kan penelitian fenomenologis di situ, seperti Adrian van Kaam, Amedeo
BAB XIII Penelitian Eksistensial-fenomenologis? 211
Giorgi, Colaizzi, William F. Fischer, atau Rolf von Eckartsberg. Kita sudah membicarakan bahwa tokoh yang paling luas dikenal di antara mereka adalah Amedeo Giorgi. Sekarang, mari kita lihat bagaimana istilah “eksistensial” bisa bisa terhubung dan menjadi akrab dengan istilah “fenomenologis”.
A. Filsafat Eksistensial (Eksistensialisme)
Dalam filsafat, eksistensialisme merupakan salah satu aliran yang mekar di akhir tahun 1800-an. Ide-ide pokok yang mendasari aliran ini bisa ditemui dalam pemikiran-pemikiran Søren Aabye Kierkegard yang kemudian dinobatkan sebagai Bapak Eksistensialisme. Kemunculan eksistensialisme pada waktu itu dirasakan sebagai sesuatu yang melenceng dari kencederungan umum dalam filsafat. Kierkegaard memang memprotes suasana filsafat di zamannya. Bagi Kierkegaard, filsafat sudah kehilangan elemen yang sangat penting, yaitu eksistensi (keberadaan) manusia di dunia. Oleh karena itu, dia menjadikan eksistensi sebagai persoalan pokok dalam filsafatnya.
Apakah eksistensi itu? Bagi Kierkegaard, eksistensi adalah situasi atau kondisi hidup di mana setiap orang dihadapkan pada kenyataan bahwa dia harus berhadapan dengan pilihan-pilihan hidupnya dengan segala risiko yang menyertai pilihan-pilihan itu. Saya, Anda, dan setiap orang yang lain terus-menerus berada dalam situasi di mana kita harus membuat pilihan-pilihan hidup. Konsekuensi dari pilihan hidup yang kita buat adalah kita harus bertanggung jawab untuk pilihan hidup kita. Apa pun pilihan yang kita ambil dalam hidup kita, kita harus bertanggung jawab secara pribadi. Tidak ada tanggung jawab kolektif. Setiap orang bertanggung jawab untuk pilihannya sendiri. Suasana hidup yang berhadapan dengan pilihan dan tanggung jawab itu disebut situasi/kondisi eksistensial. Sampai di sini, kita rangkum dulu pembicaraan kita:
"Situasi/kondisi eksistensial adalah situasi di mana setiap orang menjalani hidupnya sendiri, membuat pilihan-pilihan pribadi, dan
bertanggung jawab untuk pilihan-pilihannya itu."
Begitulah, hidup itu penuh dengan pilihan dan setiap orang pada dasar-nya bebas memilih. Tampaknya, kebebasan memilih itu adalah kebahagiaan.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup212
Bila diperiksa lebih jauh, kebebasan itu bukan kebahagiaan, tetapi kegelisahan. Semakin Anda bebas, semakin banyak pilihan yang tersaji di depan Anda. Semakin banyak pilihan yang tersaji di depan Anda, semakin banyak konsekuensi atau risiko yang akan diterima. Akibatnya, kita merasa gelisah. Kita rangkum lagi:
"Di dalam kebebasan ada kegelisahan. Semakin kita bebas, semakin kita gelisah."
Istilah “kegelisahan” yang baru saja saya gunakan adalah terjemahan Indonesia untuk kata “angest” dalam bahasa Denmark. Untuk sementara, saya memilih istilah “kegelisahan” sampai ada istilah yang lebih tepat. Dalam bahasa Jerman disebut Angst, dalam bahasa Prancis disebut angoisse, dan dalam bahasa Inggris disebut anguish. Angest/Angst/angoisse/anguish punya beberapa makna, seperti kecemasan, ketakutan, kegelisahan, kesedihan, kesusahan, derita, stres, duka. Intinya, ada perasaan tidak menentu yang membuat suasana hati menjadi tidak tenteram. Angest (kegelisahan) itu adalah warna dasar kehidupan manusia. Meski demikian, kegelisahan bisa juga menjadi undangan untuk memeriksa hidup lewat pertanyaan-pertanyaan pokok tentang kehidupan. Pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari kegelisahan itu disebut “pertanyaan-pertanyaan eksistensial”. Kita rangkum lagi:
"Situasi eksistensial menimbulkan pertanyaanpertanyaan eksistensial."
Pertanyaan eksistensial itu subjektif, tergantung pada kegelisahan apa yang mengusik seseorang dalam hidupnya. Berikut ini adalah beberapa contoh pertanyaan eksistensial yang sering ditemui saat seseorang mempertanyakan hidupnya.
• Mengapaaku merasa kesepian di tengah banyak orang?• Adakah carauntukmembuathidupku lebih bermakna dan punya
arti? • Apakahaku bisa menikmati hidup di tengah macam-macam tekan-
an hidup?
BAB XIII Penelitian Eksistensial-fenomenologis? 213
• Mengaparelasiku dengan orang lain lebih sering menyakitkan ke-tim bang membahagiakan?
• Apaartinyabermediasosialjikahanyamembuatku gelisah?• Apasebenarnyayangaku cari dalam hidupku?• Mengapahidupku terasa kosong dan monoton?• Kemanaarahatautujuanhidupku? • Untukapaaku bekerja keras kalau hidup itu singkat saja? • Siapaaku ini sebenarnya?
Jika warna dasar hidup adalah angest/Angst/anguish/angoisse/kegelisahan, apakah ada jalan keluarnya? Kierkegaard mendorong setiap orang untuk berkembang menjadi pribadi yang religius. Menjadi religius berarti menjalin hubungan pribadi dan subjektif dengan Tuhan. Penyebab kegelisahan adalah keterasingan dari Tuhan. Semakin manusia terasing dari Tuhan, semakin dia hidup dalam Angst/anguish/angoisse/kegelisahan.
B. Istilah “Eksistensial-fenomenologis”
Sejauh ini, saya sudah menampilkan beberapa tema pokok dalam eksis-tensialisme, yaitu kebebasan, pilihan hidup, kegelisahan, situasi eksistensial, pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Kita sekarang bisa bertanya: apa hubungan semua itu dengan fenomenologi?
Eksistensialisme membantu kita memahami kondisi hidup manusia di dunia, yaitu setiap orang membuat pilihan subjektif dan pribadi dalam hidupnya dan bertanggung jawab untuk pilihannya yang subjektif dan pribadi itu. Setiap pilihan hidup adalah pengalaman hidup yang menarik untuk dimengerti atau dipahami. Pertanyaan yang kemudian muncul: Jika pilihan hidup itu adalah pengalaman yang subjektif dan pribadi, adakah cara untuk memahami pengalaman yang subjektif dan pribadi itu? Ada caranya. Ada jalannya. Ada metodenya. Metode itu adalah metode fenomenologis.
Dalam penelusuran literatur yang saya lakukan, saya menemukan dua tokoh fenomenologi yang bertanggung jawab dalam mengawinkan eksitensialisme dan fenomenologi. Mereka adalah Martin Heidegger dan Jean-Paul Sartre. Dalam buku “Existential Phenomenological Perspectives in Psychology (Perspektif Eksistensial Fenomenologis dalam Psikologi)”, Valle dan Halling (1989:6) menulis begini.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup214
Teks Asli
The Danish thinker Søren Kierkegaard (1813-1855) is generally regarded as the founder of existential philosophy, whereas Edmund Husserl (1859-1938), a German philosopher, is credited as the primary proponent of phenomenology. For Kierkegaard, it was imperative that philosophy address itself to the concrete existence of the individual person and attempt to elucidate the fundamental themes with which human beings invariably struggle. Husserl ’s aim was more academic: phenomenology meant the rigorous and unbiased study of things as they appear so that one might come to an essential understanding of human consciousness and experience. Then development of specific methods for studying human experience is one of the primary contributions of phenomenology.
Transkreasi
Pemikir Denmark Søren Kierkegaard (1813-1855) umumnya dipandang sebagai peletak dasar filsafat eksisten-sial, sementara Edmund Husserl (1859-1938), seorang filsuf Jerman, dinobat kan sebagai tokoh utama fenomenologi. Bagi Kierkegaard, filsafat harus mengarahkan perha-tian nya pada eksistensi konkret setiap orang secara pribadi dan berupaya me nun jukkan dengan jelas tema-tema pokok yang diperjuangkan setiap orang dalam caranya masing-masing. Tujuan Husserl lebih bersifat akademis: feno-menologi berarti penelitian yang ketat (rigorous) dan tidak bias tentang apa saja yang muncul dalam kesadaran pribadi setiap orang sehingga peneliti bisa sampai pada pemahaman yang paling dasar (pemahaman esen sial) tentang kesadaran dan penga laman manusia. Oleh karena itu, pengem-bang an metode-metode yang secara khusus mempelajari pengalaman manu sia adalah salah satu sumbangan penting dari fenomenologi.
Penulis mengungkapkan bahwa eksistensialisme memberikan sumbangan pemikiran tentang manusia yang menjalani hidupnya secara unik dan fenomenologi memberikan sumbangan untuk lahirnya metode penelitian yang memahami pengalaman subjektif dan pribadi manusia. Bagaimana dua aliran filsafat ini bisa berkolaborasi? Polinghorne (2007:43) melihat peran Heidegger dalam kolaborasi itu, seperti yang diungkapkannya berikut ini.
BAB XIII Penelitian Eksistensial-fenomenologis? 215
Teks Asli
With Martin Heidegger’s (1927/1962) investigation, Being and Time, pheno me-nological philosophy began to merge with philosophy of existence. Existentialism, whose roots go back to Kierkegaard and beyond (Friedman, 1964), can be de-fined by its central theme, existence, a term used in a new, more limited sense by Kierkegaard, for the way in which a single individual experiences his or her being-in-the-world. Existential pehnomenology maintains that existence can be approached phenomenologically and studied as one phenomenon among others in its essential structures.
Transkreasi
Dengan munculnya hasil penelitian Heidegger lewat buku Being and Time (Ada dan Waktu), filsafat fenome-nolo gis mulai menyatu dengan filsa-fat eksistensial. Eksistensialisme, yang akarnya bisa ditelusuri sampai ke Kierkegaard, bisa didefinisikan menu rut tema pokoknya, yaitu eksis tensi. Istilah “eksistensi” ini diguna kan oleh Kierkegaard dalam penger tian yang baru dan lebih ter-batas. Maknanya adalah cara setiap orang mengalami keberadaannya di dunia ini. Fenomenologi eksistensial berpandangan bahwa eksistensi bisa didekati secara fenomenologis dan diteliti sebagai salah satu fenomena yang ingin dimengerti esensinya.
Pandangan Heidegger membawa pengaruh bagi Jean-Paul Sartre, filsuf lain yang juga berperan dalam memadukan eksistensialisme dan feno me nologi di Prancis. Dalam buku Phenomenology and Existentialism (Fenomenologi dan Eksistensialisme), Robert C. Solomon (1980:x) menulis tentang peran Sartre sebagai berikut.
Teks Asli
Jean-Paul Sartre is the best known of the many philosophers who have referred to their work as “phenomenology”. He is also the most articulate spokesman for the popular philosophy of “existentialism”. As a result, commentators on recent European philosophy have bonded pheno-menology and existentialism together in a common-law marriage of association.
Transkreasi
Oleh banyak filsuf, pemikiran Jean-Paul Sartre dikenal sebagai fenomeno-logi. Dia juga juru bicara yang paling lantang untuk filsafat populer “eksis-ten sialisme”. Akibatnya, banyak komen tator tentang filsafat Eropa telah meyatukan fenomenologi dan eksistensialisme dalam ikatan asosiasi. [Intinya, Sartre dipandang
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup216
sebagai filsuf yang sangat berperan dalam menyatukan filsafat eksistensial dan filsafat fenomenologis menjadi filsafat eksistensial-fenomenologis).
Seperti apa persisnya pandangan eksistensial-fenomenologis dari Hei-deg ger dan Sartre? Heidegger melihat manusia sebagai makhluk yang terlempar ke dalam dunia. Manusia berada di dalam dunia dalam keadaan terlempar ( Jerman: geworfenheit; Inggris: thrownness). Manusia tidak dilempar, tetapi terlempar. Paling tidak, ada dua realitas yang muncul dalam keadaan terlempar ini.
1. Realitas yang pertama adalah bahwa dalam keadaan terlempar itu, manusia tiba-tiba saja sudah menemukan dirinya berada dalam dunia (in-der-Welt sein). Dia tidak punya ingatan dari mana dia datang dan dia tidak tahu mau ke mana dia pergi. Situasi ini menimbulkan angest (kegelisahan).
2. Realitas hidup yang kedua adalah bahwa dalam keadaan terlempar itu, manusia kemudian melihat dirinya sebagai makhluk yang berjalan menuju kematian (Sein zum Tode). Kesadaran akan datang-nya kematian ini juga membuat manusia hidup dalam angest (kegelisahan).
Sartre menerima pandangan Heidegger tentang keterlemparan itu. Bagi Sartre, keterlemparan adalah tonggak bagi manusia untuk sadar bahwa dia pada dasarnya adalah makhluk yang bebas menentukan arah hidupnya. Manusia bebas melakukan apa saja yang dia mau. Manusia bebas memilih mau berbuat apa. Bagaimanapun, ada konsekuensi yang harus diterima dari setiap perbuatan bebas itu. Situasi bebas yang punya konsekuensi ini potensial menimbulkan Angest/Angst/angoisse/anguish/kecemasan. Sartre (1916:29) mengatakan:
BAB XIII Penelitian Eksistensial-fenomenologis? 217
Teks Asli
... man is condemned to be free. Condemned, because he did not create himself, yet is nevertheless at liberty, and from the moment that he is thrown into this world he is responsible for everything he does.
Transkreasi
... manusia dikutuk untuk menjalani hidupnya dengan bebas. Saya mengatakan dikutuk karena manusia tidak menciptakan dirinya sendiri. Meski demikian, manusia itu bebas dan sejak dia terlempar ke dalam dunia ini, dia bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang dia perbuat.
Lalu apa hubungan pandangan eksistensial Sartre itu dengan feno-menologi? Sartre menyoroti pengalaman manusia yang bebas membuat pilihan dalam hidupnya, tetapi harus berani menerima konsekuensi dari pilihan hidupnya itu. Fenomenologi sebagai metode riset tentang pengalaman pribadi terhubung dengan pandangan Sartre itu. Mari kita perjelas lagi.
• Dalam keadaan stres, manusia bebas memilih cara melepaskanstresnya. Dalam kebebasannya itu, dia bisa mengonsumsi minuman beralkohol dengan konsekuensi bahwa dia akan mengalami kecan-duan. Nah, peneliti fenomenologis-eksistensial bisa meneliti penga-laman kecanduan alkohol.
• Dalamkehidupanberumahtangga,ayahsebagaikepalarumahtanggabebas memilih cara mendidik anak-anaknya. Dalam kebebasannya itu, dia bisa menggunakan kekerasan fisik dalam rumah tangga pada anak-anaknya dengan konsekuensi menyaksikan gangguan perkembangan anak di kemudian hari. Peneliti fenomenologis-eksistensial bisa meneliti pengalaman kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga itu.
• Dalam mengikuti gaya hidup urban, wanita bebas memilih gayahidup yang bisa dia nikmati. Dalam kebebasannya itu, dia bisa memilih untuk tidak menikah agar sukses dalam kariernya. Peneliti fenomenologis-eksistensial bisa meneliti pengalaman menjadi wanita sukses yang tidak menikah.
Nah, banyak pengalaman hidup manusia terhubung dengan kebebasan dan konsekuensi dari kebebasan itu. Kebebasan melakukan sesuatu adalah
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup218
pengalaman dan konsekuensi dari kebebasan itu juga adalah pengalaman. Fenomenologi bisa masuk ke situ untuk melakukan penelitian tentang pengalaman manusia yang bebas dan harus menanggung konsekuensi dari kebebasannya itu. Seperti itulah jalinan keterhubungan antara eksistensialisme dan fenomenologi di Eropa.
Di Amerika Serikat, ikatan eksistensialisme dan fenomenologi ditemui dalam aliran psikologi humanistik, khususnya lewat teori dan terapi humanistik dari Carl Ransom Rogers atau yang dikenal juga dengan nama person-centered therapy (terapi yang berpusat pada pribadi). Diterapkan dalam cara apa pun, pendekatan eksistensial-fenomenologis selalu memberikan tempat khusus pada upaya memahami bagaimana setiap orang menghayati hidupnya masing-masing.
Sebagai penutup bab ini, saya ingin menampilkan ucapan dari Sartre dan Rogers yang bisa menjadi permenungan kita dalam memahami situasi eksistensial manusia dalam menjalani hidupnya. Saya akan memulai dengan Sartre yang melihat kesulitan manusia untuk berkembang secara alamiah karena terkekang oleh situasi yang sarat dengan penilaian (judgement) dari orang lain. Sartre (1973) mengatakan:
Teks Asli
J’ai voulu dire “l ’enfer c’est les autres” … Quand nous pensons sur nous, quand nous essayons de nous connaître, au fond nous usons des connaissances que les autres ont déjà sur nous, nous nous jugeons avec les moyens que les autres ont, nous ont donné, de nous juger …. Et il existe une quantité de gens dans le monde qui sont en enfer parce qu’ils dépendent trop du jugement d’autrui.
Transkreasi
Saya ingin mengatakan, “Orang lain adalah neraka [siksaan]”… Saat kita merenungkan siapa diri kita, saat kita berusaha mengenal diri kita, kita pada dasarnya mengenal diri kita berdasarkan komentar-komentar orang lain tentang diri kita, kita menilai diri kita sendiri berdasarkan penilaian-penilaian yang diberikan orang lain pada kita [Kita tidak menjadi diri kita sendiri]…. Dan ada begitu banyak manusia di dunia ini yang berada dalam neraka [tersiksa] karena hidup mereka terlalu tergantung pada penilaian orang lain.
BAB XIII Penelitian Eksistensial-fenomenologis? 219
Beberapa penelitian fenomenologis cukup sering menampilkan tema yang terkait dengan rasa malu, rasa tidak berarti, rasa tidak dihargai, atau rasa dikekang oleh lingkungan. Tema-tema seperti itu adalah tema-tema eksistensial yang muncul dalam lingkungan yang tidak menunjang pertumbuhan diri yang positif.
Tidak jarang terjadi, peneliti bertemu dengan partisipan yang berada dalam situasi eksistensial di mana dia merasa tidak mengerti dengan dirinya sendiri dan merasakan kebutuhan untuk dikuatkan dan dimengerti. Kehadiran peneliti fenomenologis bisa membawa dampak terapeutik. Artinya, peneliti tidak hanya datang menemui partisipan untuk mengumpulkan data, tetapi juga menjadi pendengar yang baik saat partisipan bercerita tentang situasi eksistensialnya atau kesusahan hidupnya. Dari Carl Rogers (1980: 160) kita mendapat pesan tentang pentingnya mengembangkan komitmen untuk memahami orang lain yang berada dalam situasi eksistensial.
Teks Asli
When the other person is hurting, confused, troubled, anxious, alienated, terrified; or when he or she is doubtful of self-worth, uncertain as to identity, then understanding is called for. The gentle and sensitive companionship of an empathic stance… provides illumination and healing. In such situations deep understanding is, I believe, the most precious gift one can give to another.
Transkreasi
Ketika orang lain terluka, bingung, galau, cemas, terasing, takut; atau ketika dia tidak lagi melihat dirinya berharga, merasa tidak yakin dengan identitasnya, maka pengertian [dari kita] diperlukan. [Bila kita bisa] Hadir bagi mereka dalam kelembutan dan kepekaan dengan sikap empatik ... [maka kehadiran kita itu] akan memberikan pencerahan dan kesembuhan. Dalam situasi-situasi [suram] seperti itu, saya percaya bahwa pemahaman yang dalam adalah hadiah yang paling berharga yang bisa kita berikan pada orang lain.
Jika pernyataan Jean-Paul Sartre dan Carl Rogers tersebut digabungkan (pernyataan yang dicetak tebal), maka kita akan bertemu dengan kualitas yang diharapkan berkembang pada peneliti fenomenologis saat bertemu
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup220
dengan orang lain, termasuk partisipan-partisipan dalam penelitiannya. Kualitas itu adalah sebagai berikut.
Teks Asli
... il existe une quantité de gens dans le monde qui sont en enfer parce qu’ils dépendent trop du jugement d’autrui .... In such situations deep understanding is, I believe, the most precious gift one can give to another.
Transkreasi
... ada begitu banyak manusia di dunia ini yang berada dalam neraka [hidup dalam kegelisahan dan rasa takut] karena hidup mereka terlalu tergantung pada penilaian orang lain [Mereka tidak menjadi diri sendiri] .... Dalam situasi-situasi [suram] seperti itu, saya percaya bahwa pemahaman yang dalam adalah hadiah yang paling berharga yang bisa kita berikan pada orang lain.
Jika ada pertanyaan, apakah penelitian fenomenologis itu? Secara akademis, saya akan menjawab bahwa penelitian fenomenologis adalah salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang awalnya berkembang dalam psikologi. Secara akademis saya menjawab begitu, tetapi secara pribadi, saya akan mengatakan, “Penelitian fenomenologis adalah jalan yang ditawarkan kepada saya dalam menemui orang lain, mendengarkannya, dan memahaminya di jalan hidup yang sedang dia tempuh”. Inilah alasan buku ini diberi judul:
“Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup”
221
BAB XIV
Pertanyaan-pertanyaan Frekuen
Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan maha-siswa dalam proses supervisi penelitian fenomenologis. Jawaban yang saya berikan di sini sebenarnya sudah ada dalam buku ini, sehingga saya kadang-kadang merujuk ke bab tertentu untuk pemahaman lebih jauh.
Apakah kita bisa menjalankan penelitian fenomenologis tanpa belajar filsafat fenomenologis?
Penelitian fenomenologis bisa kita katakan sebagai penerapan praktis dari filsafat fenomenologis. Dalam buku “Fenomenologi: Jalan Memahami Pengalaman Hidup”, saya memang tidak banyak berbicara tentang filsafat fenomenologis. Buku ini ditulis dengan niat memberikan penjelasan praktis tentang fenomenologi bagi peneliti-peneliti dalam disiplin psikologi pada khususnya dan disipin-disiplin lain dalam ilmu-ilmu kemanusiaan (human sciences) yang ingin memanfaatkan fenomenologi sebagai metode riset.
Meski menghindari pembicaraan tentang filsafat, saya tetap menying-gungnya di beberapa bagian. Penelitian fenomenologis tidak mungkin bisa dibicarakan lepas sepenuhnya dari filsafat fenomenologis. Jika tertarik dengan filsafat di balik penelitian fenomenologis, sudah begitu banyak buku filsafat fenomenologis yang beredar. Untuk membantu mahasiswa psikologi yang ingin memahami dasar-dasar filosofis dari penelitian fenomenologis, saya juga menulis buku lain yang berjudul “Fenomenologi: Filsafat untuk Riset Fenomenologis”. Sebenarnya, tidak ada yang baru dalam buku itu
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup222
selain menarik keluar konsep-konsep kunci dalam filsafat fenomenologis yang relevan bagi penelitian fenomenologis dalam psikologi. Oleh karena itu, sudah betul bahwa fakultas psikologi menawarkan filsafat fenomenologis sebagai mata kuliah. Bila penelitian kuantitatif butuh diberi pemahaman tentang dasar-dasar statistika, maka penelitian fenomenologis juga butuh diberi pemahaman dasar tentang filsafat fenomenologis.
Lalu, apa keterkaitan antara psikologi dan fenomenologi? Kalau kita membaca sejarah psikologi, tidak sulit untuk mendapatkan data historis yang menunjukkan bahwa masa kemunculan psikologi adalah masa kemunculan fenomenologi. Tokoh-tokoh fenomenologi hidup sezaman dengan tokoh-tokoh yang merintis psikologi modern. Menjelang akhir tahun 1800-an, psikologi ingin menjadi objektif seperti ilmu alam, khususnya objektif seperti ilmu faal atau fisiologi. Wajar saja bila laboratorium-laboratorium psikologi didirikan. Yang terkenal pada waktu itu adalah laboratorium psikologi di Universitas Leipzig yang didirikan oleh Wilhelm Wundt yang umumnya dikenal sebagai Bapak psikologi modern.
Pendiri fenomenologi Edmund Husserl pernah mengeritik metode penelitian yang digunakan oleh Wilhelm Wundt di laboratoriumnya. Oh iya, saya belum menjelaskan bahwa baik fenomenologi Husserl maupun psikologi Wundt repot dengan kesadaran manusia yang dalam bahasa Jerman disebut Bewusßtsein atau consciousness dalam bahasa Inggris. Meski keduanya sibuk membicarakan kesadaran, Husserl tidak sepakat dengan Wundt yang memecah kesadaran manusia menjadi elemen-elemen. Bagi Husserl, kesadaran manusia itu mengalir sehingga tidak bisa dipecah-pecah. Kita bisa mengibaratkan kesadaran itu dengan aliran sungai. Dari kejauhan kelihatannya stagnan dan tidak mengalir, tetapi bila kita melihat dari dekat, alirannya jelas sekali. Nah, Husserl menawarkan metode memahami kesadaran manusia yang mengalir itu. Metode itulah yang kita kenal dengan nama metode fenomenologis.
Fenomenologi bisa kita posisikan sebagai pengingat (reminder) bagi psikologi untuk berhati-hati meneliti kesadaran yang mengalir itu. Peneliti fenomenologis meneliti jiwa (kesadaran) partisipan dengan melibatkan jiwa (kesadaran) peneliti. Jadi, kesadaran peneliti bertemu dengan kesadaran partisipan. Kesadaran peneliti terhubung dengan kesadaran
BAB XIV Pertanyaan-pertanyaan Frekuen 223
partisipan. Kesadaran ketemu kesadaran. Ini riskan sekali. Carl Gustav Jung menyebutnya “lingkaran setan (vicious circle)”.
Sejauh ini, kita sudah bertemu dengan dua versi penelitian fenomenologis, yaitu penelitian fenomenologis deskriptif (PFD) dan interpretative phenomenological analysis (IPA). Dalam kedua versi penelitian fenomenologis itu, peneliti menginterpretasikan kesadaran partisipan sambil memeriksa kesadarannya sendiri. Fenomenologi mengakui subjektivitas sebagai pintu masuk menuju pemahaman tentang pengalaman manusia. Penelitian fenomenologis tidak meminta peneliti menjadi pribadi yang hebat menilai orang lain. Peneliti fenomenologis diharapkan menjadi orang yang hebat dalam melihat dirinya sendiri terlebih dahulu. Karena itulah Husserl menekankan epochē atau yang dalam bahasa Jerman disebut Einklämmerung atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan bracketing atau suspension. Semua istilah itu (epochē, Einklämmerung, bracketing, suspension) pada intinya berarti imbauan bagi peneliti untuk memeriksa diri dan membersihkan diri dari kecenderungan menilai pengalaman orang lain dengan pengetahuan yang sudah terlanjur bercokol dalam diri kita.
Ada yang menarik tentang pribadi Husserl, yaitu dia pernah menyebut dirinya sebagai pemula yang abadi. Bahasa Jermannya ewige Anfänger atau eternal beginner dalam bahasa Inggris. Artinya, dia selalu berusaha menjaga persepsi yang segar dalam memahami pengalaman orang lain. Dalam keadaan epochē, penghambat-penghambat dalam diri sendiri dibersihkan. Jika penghambat itu disingkirkan, kita bisa melihat tanpa penghambat. Penglihatan tanpa pengahalang itu disebut “das unmittelbare Sehen” dalam bahasa Jerman atau kita mungkin bisa menyebutnya unobstructed view dalam bahasa Inggris. Itulah persepsi yang segar.
Memiliki persepsi yang segar terdengar mengasyikkan. Perlu disadari betul bahwa melihat dengan segar pengalaman orang lain itu bukan perkara gampang. Pikiran kita sering kali sudah kotor oleh “rasa tahu” dan menjadi kotor banget oleh “rasa sok tahu”. Tapi bila kita berhasil menyingkirkan rasa tahu atau sok tahu itu, apa yang terjadi pada kita? Kita bebas dari rasa tahu dan sok tahu itu. Kita bisa melihat orang lain dalam keasliannya. Ini mirip dengan orang yang melihat pemandangan indah dari dalam mobil dan membuka jendela kaca mobil atau berhenti dan keluar dari mobil untuk melihat langsung. Kurang lebih begitulah intinya. Penelitian fenomenologis
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup224
mengajak peneliti melihat pengalaman partisipan dalam keaslian, tanpa perantara. Melihat tanpa perantara berarti melihat jernih, apa adanya. Seperti itulah cara fenomenologi memahami objektivitas. Awalnya subjektif, lalu epochē, lalu objektif. Kita bisa menyebut objektivitas dalam fenomenologi sebagai objektivitas yang berbasis subjektivitas. Saya kira, itulah yang dicita-citakan filsafat fenomenologis dan ingin diterapkan oleh peneliti-peneliti fenomenologis.
Saat saya menganalisis data, ada teman yang berkomentar bahwa penelitian kualitatif aneh. Analisisnya kok subjektif dan gak jelas yah?
Temanmu itu benar. Kalau kesadaran manusia ketemu benda sih bisa jelas. Kita bisa mengukurnya dengan macam-macam teknik penghitungan, seperti bila kita mengukur panjang meja atau mengukur berat badan. Tetapi bila kesadaran ketemu kesadaran, kita perlu berhati-hati soal kejelasan. Jadi, apa yang dikatakan temanmu itu benar. Dalam fenomenologi, kita melihat manusia memang tidak jelas sehingga kita perlu mengupayakan kejelasan. Fenomenologi menawarkan cara untuk mengupayakan kejelasan itu. Caranya adalah dengan mengakui subjektivitas. Seperti yang sudah sering kita bicarakan, subjektivitas tidak perlu ditolak. Tapi tolong, pahami subjektivitas dalam fenomenologi dengan menggunakan perspektif fenomenologis. Dalam fenomenologi, peneliti perlu sadar dan mengakui bahwa dia subjektif. Dengan sadar bahwa dia subjektif, dia mau memeriksa dirinya dan membersihkan dirinya dari potensi-potensi yang bisa merusak keaslian pengalaman partisipan.
Apa yang dikatakan Carl Rogers dan Carl Gustav Jung di awal buku ini adalah kebenaran dari perspektif fenomenologis. Psikologi harus objektif, benar-benar harus objektif. Caranya adalah peneliti perlu mengakui subjektivitasnya yang rentan mengotori penglihatannya pada orang lain. Saya kira, inilah alasan Edmund Husserl mengatakan bahwa penelitian fenomenologis pada dasarnya adalah penelitian reflektif. Istilah “refleksi” berasal dari kata Latin reflectere yang berarti membungkuk seperti bila orang Jepang memberi hormat. Itu artinya kita mau melihat diri kita dengan rendah hati. Jadi, betul bahwa penelitian fenomenologis itu subjektif. Bukan subjektif dalam pengertian semauku sendiri, serampangan, dan asal-asalan.
BAB XIV Pertanyaan-pertanyaan Frekuen 225
Itulah alasan ketika ada yang mempersoalkan subjektivitas, saya mengatakan “Fakta yang paling objektif tentang manusia adalah bahwa manusia itu pada dasarnya subjektif ”.
Mengapa hanya ada dua versi?
Sebenarnya bukan hanya ada dua. Selain versi penelitian fenomenologis deskriptif (PFD) dan IPA, masih ada lagi yang disebut versi fenomenologis naratif. Versi penelitian fenomenologis apa pun yang berkembang tetap mengambil makanannya dari fenomenologi, khususnya Edmund Husserl yang menekankan pada deskripsi pengalaman dan Martin Heidegger yang menekankan pada penafsiran atau interpretasi atau hermeneutika. Keduanya adalah referensi induk dalam fenomenologi. Amedeo Giorgi, peletak dasar PFD, menyebut Husserl dan Heidegger sebagai dua raksasa fenomenologi. Husserl adalah Bapak Fenomenologi dan Heidegger adalah muridnya. Sampai sekarang pun, fenomenologi tetap dibicarakan dan dua nama itu tetap saja muncul.
Nah, PFD dikembangkan Giorgi dengan “cita-cita” untuk setia pada Husserl yang ingin mendeskripsikan pengalaman secara murni. Giorgi mengembangkan PFD sejak tahun 1970-an. Pada tahun 1990-an, ada pengembangan fenomenologis lain yang sejalan dengan fenomenologi Martin Heidegger yang sekarang populer dikenal dengan nama IPA (interpretative phenomenological analysis). Jika Husserl mengajak kita menembus pengalaman partisipan sampai ke intinya dan mendeskripsikan inti itu, maka Heidegger mengajak kita berselancar dalam dunia pengalaman partisipan sambil menceritakan apa yang kita dapatkan saat berselancar. Kedua versi itu (PFD dan IPA) sepakat bahwa epochē perlu dijalankan dalam penelitian fenomenologi. Meski demikian, keduanya berbeda dalam cara menjalankan epochē.
Dua versi itu umum ditemui dalam banyak riset. Tapi sejauh ini, versi IPA tampaknya banyak digunakan. Saya kira, penyebabnya adalah buku Jonathan A Smith, Flowers, dan Larkin yang berjudul “Interpretative Phenomenological Analysis” yang memberi panduan yang jelas tahap demi tahap tentang cara menjalankan IPA. Perlu diingat bahwa IPA bukan satu-satunya versi dalam penelitian fenomenologis yang menekankan pada proses
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup226
interpretatif. Masih ada versi lain, seperti yang dikembangkan oleh van Manen yang banyak digunakan dalam pedagogi. IPA itu adalah versi yang banyak digunakan untuk penelitian fenomenologis interpretatif; sementara versi yang dikembangkan Giorgi banyak digunakan untuk versi fenomenologis deskriptif. Perbedaan di antara mereka bukan persoalan mendasar. Variasi boleh saja asalkan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar fenomenologi.
Apakah ada cara yang pakem dalam menulis judul penelitian fenome-nologis?
Judul penelitian fenomenologsi bisa dibunyikan beragam atau bervariasi. Di balik keberagaman atau variasi itu, prinsip dasarnya adalah sorotan pada pengalaman subjektif dari orang yang mengalami langsung suatu fenomena. Kita sudah berbicara banyak tentang apa itu fenomena dalam Bab II. Judul fenomenologi umumnya sudah memberi gambaran tentang pengalaman apa yang ingin diteliti. Jadi, konsep kuncinya adalah pengalaman dari orang yang mengalami langsung suatu fenomena.
Karena itu, tidak perlu heran bila banyak judul penelitian fenomenologis mengandung kata pengalaman langsung (lived experience). “Penelitian fenomenologis tentang pengalaman ….(Phenomenological study of the lived experience of ….)” adalah bunyi judul yang umum ditemui. Ada juga yang membuat variasi judul dengan menggunakan istilah-istilah lain seperti, investigasi fenomenologis tentang, ekplorasi fenomenologis tentang, eksaminasi fenomenologis tentang, riset fenomenologis tentang, kajian fenomenologis tentang. Ada juga yang membunyikannya “Pengalaman sebagai …”, “Pengalaman menjadi ….”, “Persepsi tentang …”, “Arti tentang…”, “Makna tentang …”. Nah, banyak sekali. Boleh saja berkreasi dalam membuat judul asalkan bisa dipertanggungjawabkan ke-fenomenologis-annya. Kita sudah membicarakan formulasi judul di banyak tempat. Kita membicarakan sekilas tentang judul itu di Bab I dan membicarakan secara khusus di Bab III (judul untuk IPA) dan Bab IV (judul untuk PFD). Perumusan judul juga sudah kita bahas lebih jauh di Bab XII dan Bab XIII (judul dengan istilah eksistensial).
BAB XIV Pertanyaan-pertanyaan Frekuen 227
Dalam analisis data kita diminta mencari tema. Bisa diperjelas lagi arti tema dalam penelitian fenomenologis?
Penelitian kualitatif itu induktif atau bergerak dari yang spesifik menuju yang general, dari yang khusus ke yang umum. Peneliti kualitatif menjalankan analisis dari data yang banyak dan kemudian disaring. Penelitian fenomenologis sebagai bagian dari penelitian kualitatif juga bergerak secara induktif seperti itu. Artinya, kita mengawali analisis fenomenologis dari informasi yang banyak dalam transkrip. Ada saatnya kita mendapatkan banyak tema yang kemudian disaring lagi menjadi tema-tema yang lebih umum. Dalam IPA, kita menyaring transkrip menjadi tema-tema emergen dan kemudian mengerucut menjadi tema-tema superordinat. Dalam PFD, kita mengenal pergerakan dari transkrip menuju tema esensial atau tema invarian. Tidak perlu bingung dengan banyaknya istilah untuk tema. Gunakan istilah-istilah untuk tema itu menurut konteksnya. Untuk penelitian dengan IPA, gunakan istilah-istilah IPA. Untuk penelitian dengan PFD, gunakan istilah-istilah PFD. Seperti yang sudah kita lihat, tema umumnya berupa kata atau frasa.
Apakah interview guide harus dibaca saat wawancara?
Tidak. Interview guide itu yah guide. Di Inggris, interview guide itu dibunyikan interview schedule. Interview guide atau interview schedule itu hanya alat bantu saja yang digunakan untuk memandu. Situasi lapangan menuntut kreativitas dan fleksibilitas peneliti. Lagi pula, interview guide itu dibuat untuk persiapan pelaksanaan wawancara semi-terstruktur. Kalau ingin mengajukan pertanyaan selama wawancara persis seperti yang ditulis, gunakan wawancara terstruktur. Tapi sejauh yang saya ketahui dan temui dan alami sendiri, penelitian fenomenologis tidak mengakomodasi wawawancara terstruktur karena bisa menghambat aliran pengalaman dari partisipan. Panduan wawancara sebaiknya dihapalkan sebelum ke lapangan agar tidak menjadi “kertas pengganggu” selama wawancara berjalan.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup228
Apakah pengumpulan data cukup dengan wawancara?
Pengumpulan data umumnya menggunakan wawancara. Dengan wa-wan cara, kita menarik keluar pengalaman partisipan dan mentranfor masi-kannya menjadi transkrip. Bagaimanapun, fokus kita adalah pengalaman. Wawancara memang dominan dilakukan, tetapi bukan satu-satunya cara untuk mengakses pengalaman. Diari atau buku harian juga bisa menjadi pintu masuk untuk mengakses pengalaman langsung seseorang. Pernyataan seseorang mengenai gambar-gambar yang dilukisnya juga bisa dijadikan materi analisis data. Bahkan, jika kita punya pengetahuan yang cukup tentang psikologi mimpi, kita bisa mengembangkan penelitian fenomenologis untuk tujuan interpretasi mimpi dalam istilah Freud atau analisis mimpi dalam istilah Jung. Kita, misalnya, mendapatkan cerita-cerita mimpi dari partisipan yang kemudian kita elaborasi dengan teknik asosiasi. Hasil elaborasi itu kemudian dianalisis dengan menggunakan versi fenomenologis. Fantasi, imajinasi, dan gambar-gambar dalam mimpi juga adalah fenomena yang bisa diteliti secara psikologis.
Apakah wawancara harus face-to-face?
Untuk peneliti pemula, saya terpaksa harus mengatakan “harus” face-to-face. Untuk peneliti yang lebih berpengalaman, wawancara langsung tetap disarankan. Perjumpaan langsung dengan orang lain memungkinkan kita menangkap dan mengamati respons-respons penting selama wawancara berlangsung, seperti anggukan kepala, desahan napas, mata yang berkaca-kaca. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk bertemu langsung, tetapi rapport sudah terbentuk atau hubungan sudah cair, wawancara yang dibantu komputer (computer-assisted interview) boleh saja dilakukan, seperti skype. Tapi ada risiko yang sering terjadi, yaitu distorsi di tengah wawancara. Seorang mahasiswa yang saya bimbing di Semarang, misalnya, pernah mewawancarai partisipan yang kemudian pindah ke Kalimantan Barat. Dia ingin melengkapi sedikit kekurangan informasi atau datanya dan saya menyarankannya lewat telepon. Bersyukur bahwa wawancara telpon berjalan lancar tanpa distorsi. Jadi, wawancara yang dimediasi peralatan digunakan dengan melihat konteks saja. Jika pertemuan langsung bisa dijalankan, lakukan wawancara face-to-face.
BAB XIV Pertanyaan-pertanyaan Frekuen 229
Berapa kali kita mewawancarai satu partisipan?
Ini pertanyaan yang saya kira paling sering ditanyakan dan dipersoalkan dalam ujian yang selama ini saya ikuti. Saya membicarakan ini di Bab VII. Saya kira sudah cukup jelas di situ kapan dan bagaimana wawancara satu kali bisa dijalankan, dan kapan serta bagaimana wawancara lebih dari satu kali harus dijalankan. Lagi-lagi, lihat konteks. Tanyakan diri sendiri dengan jujur: Apakah saya sudah mempersiapkan betul interview guide saya? Apakah rapport sudah terbentuk dengan bagus sehingga saya dan partisipan benar-benar relaks selama wawancara? Apakah selama wawancara tidak ada distorsi yang menghambat aliran informasi dari partisipan? Apakah ketika transkrip dibaca, saya merasa hasil wawancaraku sudah jelas dan memuaskan sehingga tidak perlu lagi penggalian lanjut? Jika semua itu dijawab “Ya”, saya kira wawancara sekali sudah cukup. Jika “belum”, segera tambah informasi dengan kembali menemui partisipan.
Berapa partisipan yang harus diwawancarai?
Saya pinjam saja pendapat Amedeo Giorgi yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak repot dengan strategi sampling, tetapi repot dengan strategi kedalaman analisis. Saya membicarakannya di Bab V. Secara singkat, bisa dikatakan bahwa jumlah sampel dalam penelitian fenomenologis bervariasi. Ada yang mungkin terdengar aneh di sini. Kenapa saya menggunakan istilah “sampel”? Kenapa bukan “partisipan” atau “subjek”? Kita boleh saja menggunakan istilah “sampel” tanpa niat membuat generalisasi. Nah, inilah yang membedakan istilah “sampel” dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak punya niat untuk melakukan generalisasi. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti punya niat menggeneralisasi. Tapi kalau masih punya aggapan bahwa sampel adalah bagian dari populasi dan harus digeneralisasikan, ya tinggal ganti istilah saja menjadi partisipan atau subjek.
PFD menegaskan jumlah sampel atau partisipan lebih dari 3 karena tujuannya adalah mendapatkan esensi dari pengalaman-pengalaman partisipan. Ingat bahwa PFD ingin menemukan esensi (inti) dari pengalaman. Klaim bahwa peneliti menemukan esensi memang kurang kuat bila jumlah partisipan kurang dari tiga. Dalam IPA, jumlah tiga sudah dianggap
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup230
bagus karena tujuannya adalah analisis yang detail dan mendalam untuk masing-masing partisipan. Dalam kasus-kasus yang sangat langka di mana partisipan memang sulit ditemui atau diakses, jumlah satu partisipan bahkan dibolehkan. IPA tidak mencari esensi pengalaman, tetapi hanya melaporkan pengalaman masing-masing partisipan sambil melihat keterhubungannya sekaligus keunikannya.
Dalam psikologi, kita mengenal terapi eksistensial. Viktor Frankl, misalnya, mengemukakan istilah kekosongan eksistensial dan frustrasi eksistensial. Apakah ada hubungannya dengan penelitian eksistensial-fenomenologis?
Viktor Emil Frankl punya pengalaman eksistensial di kamp konsentrasi Jerman, pengalaman yang menggugah hati. Itu terjadi di masa Perang Dunia II. Frankl mengalami sendiri apa itu situasi eksistensial (hidup yang diwarnai kegelisahan) dan perjuangan eksistensial (mencari makna hidup dalam kegelisahan). Lewat pengalamannya mengolah hidup, dia melahirkan logoterapi. Istilah logos dalam bahasa Yunani punya beberapa arti. Salah satunya adalah makna (meaning). Logoterapi berarti terapi makna. Logoterapi memperlihatkan dengan jelas bagaimana penyakit mental terhubung dengan situasi eksistensial (hidup yang diwarnai kegelisahan) di dunia. Selama manusia belum menemukan makna hidupnya, selama itu pula dia gelisah. Dan, kegelisahan ini potensial memunculkan macam-macam gangguan mental. Bagaimanapun, perlu diingat bahwa Frankl berbicara tentang metode terapeutik, bukan metode riset. Selain Frankl, kita juga mengenal Carl Rogers, Bapak terapi humanistik yang menerapkan fenomenologi dan eksistensialisme dalam praktik terapeutiknya. Kalau mau lebih dalam lagi mempelajari eksistensialisme yang berkembang dalam psikologi, saya menyarankan membaca pemikiran-pemikiran Ludwig Binswanger, Medard Boss, dan Rollo May. Mereka adalah psikiater dan psikolog yang terhubung dengan filsuf Martin Heidegger.
Eksistensialisme atau filsafat eksistensial membicarakan manusia unik yang harus berjuang memahami hidupnya di dunia. Warna dasar dari kehidupan manusia di dunia ini adalah kecemasan dan kegelisahan. Manusia itu unik dalam menghadapi kegelisahan hidupnya. Pertanyaan selanjutnya,
BAB XIV Pertanyaan-pertanyaan Frekuen 231
adakah cara atau metode penelitian yang bisa membantu kita memahami manusia yang seperti itu? Nah, fenomenologi masuk sebagai metode riset yang bermanfaat dalam memahami pengalaman hidup manusia. Dalam cara itulah, eksistensialisme dan fenomenologi disinergikan menjadi eksistensial-fenomenologis.
233
G l o s a r i u m
Dalam glosarium ini, ada beberapa kata yang diambil dari bahasa Jerman dan sulit untuk diindonesiakan. Secara historis, fenomenologi lahir dan berkembang di Jerman sebelum menyebar ke Prancis dan negara-negara lain. Kata benda dalam bahasa Jerman selalu ditulis dengan huruf awal kapital (huruf besar).
aksesibilitas Salah satu pertimbangan dasar peneliti dalam menentukan partisipan/subjek
penelitian. Aksesibilitas secara harfiah berarti kemampuan untuk diakses. Dalam menjalankan penelitian fenomenologis, aksesibilitas berarti keterbukaan dan kebersediaan partisipan untuk diakses oleh peneliti.
angest Istilah dalam bahasa Denmark yang bisa diindonesiakan menjadi “kege lisahan”.
Istilah ini diperkenalkan oleh Søren Aabye Kierkegaard, Bapak eksistensialisme (filsafat eksistensial). Angest (kegelisahan) ini adalah kondisi dasar manusia dalam menjalani hidupnya di dunia. Terjemahan angest yang juga umum ditemui dalam literatur asing adalah anguish (Inggris), Angst ( Jeman), dan angoisse (Prancis). Lihat juga situasi eksistensial.
bracketing Istilah Inggris untuk epochē. Secara harfiah bracketing berarti meletakkan dalam
tanda kurung (brackets). Lihat juga epochē.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup234
coding Pemberian pemberian kode untuk data yang diperoleh dalam grounded theory
(GT). Ada tiga tahapan coding yang umum ditemui dalam literatur GT, yaitu (1) open coding, (2) axial coding, dan (3) selective coding. Tahapan itu mencerminkan pergerakan dari (1) data yang banyak, (2) memadat, lalu (3) mengerucut pada inti dari seluruh data.
Dasein Secara harfiah berarti ada di sana. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan there-
being. Istilah ini digunakan oleh Martin Heidegger untuk membicarakan manusia yang berada di dalam dunia, merasa cemas, dan secara unik memberi makna untuk hidup yang dia jalani.
demografi partisipan Penyajian ciri-ciri utama dari seluruh partisipan yang direkrut dalam penelitian,
seperti usia, pekerjaan, jumlah anak, jenis kelamin, dan seterusnya. Demografi partisipan boleh disajikan dalam bentuk tabel.
descriptive phenomenological analysis Alur analisis data yang kami kembangkan sebagai alternatif dalam menjalankan
PFD. Dalam buku ini, descriptive phenomenological analysis disingkat DPA.
deskripsi fenomenologis Deskripsi pengalaman dengan menggunakan sikap fenomenologis. Dalam
PFD, deskripsi fenomenologis ini adalah gambaran yang diberikan peneliti saat menganalisis deskripsi natural (transkrip) partisipan.
deskripsi natural Deskripsi pengalaman dengan menggunakan sikap natural. Dalam PFD,
deskripsi natural ini adalah gambaran yang diberikan partisipan saat diwawan-carai dengan menggunakan bahasa natural. Transkrip orisinal adalah bentuk tertulis dari deskripsi natural.
deskripsi struktural Deskripsi untuk struktur-struktur dasar (tema-tema esensial) yang didapatkan
dari deskripsi tekstural. Deskripsi struktural dijalankan dengan bantuan variasi imajinatif. Dalam PFD versi Moustakas, deskripsi struktural terbagi menjadi deskripsi struktural individual (deskripsi struktural per partisipan) dan deskripsi struktural komposit (deskripsi struktural seluruh partisipan).
Glosarium 235
deskripsi tekstural Deskripsi untuk tema-tema awal yang muncul dari teks (transkrip). Deskripsi
ini dijalankan dengan bantuan epochē. Dalam PFD versi Moustakas, deskripsi tekstural terbagi menjadi deskripsi tekstural individual (deskripsi tekstural per partisipan) dan deskripsi tekstural komposit (deskripsi tekstural seluruh partisipan).
DPA Lihat descriptive phenomenological analysis.
dunia kehidupan Lihat Lebenswelt.
eidos Kata Yunani yang berarti inti/esensi. Peneliti dalam PFD diharapkan
menemukan eidos dari pengalaman seluruh partisipan di akhir penelitiannya.
Einklämmerung Istilah Jerman untuk epochē. Lihat epochē.
eksistensial-fenomenologis Istilah yang menunjukkan hubungan erat antara eksistensialisme dan fenome-
nologi. Baik eksistensialisme maupun fenomenologi sibuk dengan dunia kehidupan pribadi setiap orang dalam menjalani hidupnya di dunia. Istilah “eksistensial-fenomenologis” seringkali dikaitkan dengan filsuf Martin Hei-degger dan Jean-Paul Sartre.
eksistensialisme (filsafat eksistensial) Aliran filsafat yang berkembang di akhir 1800-an dan dan dirintis oleh filsuf
Denmark Søren Aabye Kierkegard. Eksistensialisme menekankan bagaimana setiap orang menjalankan hidupnya di dunia. Setiap orang pada dasarnya hidup bebas. Dalam kebebasan itu, setiap orang harus membuat pilihan dan menanggung sendiri risiko untuk pilihan yang dia buat. Dalam suasana itu, manusia hidup dalam angest (kegelisahan). Lihat juga situasi eksistensial dan pertanyaan eksistensial.
epifani Peristiwa-peristiwa penting (signifikan) dalam kehidupan seseorang yang
punya daya atau kekuatan untuk mengubah haluan hidup.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup236
epochē Istilah yang diambil Husserl dari bahasa Yunani untuk menunjukkan pentingnya
membebaskan diri dari pengaruh pengetahuan yang sudah bercokol dalam diri sendiri saat menganalisis data. Ada beberapa istilah lain yang umum digunakan untuk epochē ini, yaitu Einklämmerung ( Jerman) dan bracketing (Inggris) yang berarti memasukkan ke dalam kurung. Istilah lain yang juga umum ditemui adalah suspension (suspensi) yang berarti "memecat" untuk sementara waktu pengetahuan yang ada dalam diri sendiri.
etnografi Disebut juga penelitian etnografis. Etnografi (penelitian etnografis) adalah
pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan shared values (nilai-nilai bersama) yang dihayati dalam suatu komunitas atau unit-unit sosial.
fenomenologi (filsafat fenomenologis) Filsafat tentang cara memahami pengalaman subjektif dari perspektif orang
yang mengalami langsung (perspektif orang pertama/first-person perspective). Bagi IPA, fenomenologi adalah salah satu dari tiga pilar IPA; sementara bagi PFD, fenomenologi adalah sumber utama, khususnya fenomenologi Edmund Husserl, pendiri fenomenologi.
filsafat eksistensial Lihat eksistensialisme.
filsafat fenomenologis Lihat fenomenologi.
first-person perspective Lihat perspektif orang pertama.
grounded theory Kadang-kadang disingkat GT adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif
yang bertujuan memunculkan teori secara induktif lewat proses coding (pemberian kode untuk data yang dikumpukan). Lihat juga coding.
hermeneutika. Salah satu pilar IPA. Hermeneutika adalah teori tentang penafsiran yang menekankan pentingnya melihat terlebih dahulu naskah secara keselu-ruhan sebelum melihat bagian-bagian naskah. Bagian hanya bermakna dalam hubungannya dengan keseluruhan. Dalam menganalisis data, peneliti IPA menjalankan hermeneutika dengan membaca keseluruhan transkrip sebelum memaknai pernyataan-pernyataan partisipan dalam transkrip.
Glosarium 237
homogenitas Salah satu pertimbangan peneliti dalam menentukan partisipan/subjek pene-
litian. Homogenitas berarti peneliti mengambil partisipan-partisipan yang memiliki ciri-ciri yang sama sebelum pengumpulan data.
horizonalisasi Salah satu langkah dalam analisis data PFD yang menggunakan versi
Moustakas. Horizonalisasi adalah proses melihat transkrip secara adil dan tidak diskriminatif. Seluruh pernyataan dalam transkrip dilihat sama pentingnya. Horizonalisasi dijalankan dalam keadaan epochē.
idiografi Salah satu pilar IPA yang menunjukkan perhatian IPA pada pengalaman
pribadi dan individual.
interpretative phenomenological analysis Umumnya disingkat IPA. Salah satu versi penelitian fenomenologis interpretatif
(interpretif ) yang bertujuan mengeksplorasi pengalaman individual secara detail dengan istilah-istilah yang sedekat mungkin dengan pengalaman partisipan.
interview guide Lihat panduan wawancara.
interview schedule Lihat panduan wawancara.
intuisi Kemampuan menangkap langsung inti (eidos) dari pengalaman partisipan
dengan bantuan variasi imajinatif. Intuisi dalam fenomenologis bekerja bila epochē dijalankan. Lihat juga variasi imajinatif.
IPA Lihat interpretative phenomenological analysis.
kasus Dalam studi kasus (case study), istilah “kasus” secara umum berarti keputusan.
Makna lain dari kasus adalah individu, organisasi, program, kegiatan, institusi, kejadian/peristiwa.
komentar deskriptif (descriptive comment). Istilah dalam IPA untuk komentar yang menggambarkan isi ucapan
partisipan.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup238
komentar eksploratoris Upaya awal peneliti dalam menafsirkan pengalaman partisipan dengan meme-
riksa dan memaknai secara detail pernyataan-pernyataan partisipan dalam transkrip. Ada tiga jenis komentar eksploratoris, yaitu komentar deskrip tif, komentar linguistis, dan komentar konseptual.
komentar konseptual (conceptual comment) Istilah dalam IPA untuk komentar yang menunjukkan pertanyaan kritis dalam
benak peneliti saat membaca pernyataan partisipan dalam transkrip.
komentar linguistis (linguistic comment) Istilah dalam IPA untuk komentar tentang bagaimana partisipan secara unik
menggunakan bahasa.
kondisi eksistensial Lihat situasi eksistensial.
konstituen Dalam penelitian fenomenologis, kita memahami partisipan dengan menjalan-
kan konstitusi (lihat juga konstitusi). Hasil dari konstitusi itu adalah konstituen-konstituen. Konstituen bisa dikatakan sebagai tema yang didapatkan dalam proses analisis. Istilah ini umum ditemui dalam PFD versi Giorgi. Lihat juga konstitusi.
konstitusi Berasal dari bahasa Latin constituere yang berarti membangun. Konstitusi
berarti upaya membangun pemahaman tentang pengalaman partisipan. Dalam penelitian fenomenologis, konstitusi berarti upaya peneliti memaknai penga-laman partisipan.
konstruktivisme Perspektif dalam psikologi yang menyatakan bahwa cara seseorang melihat
dunia tergantung pada pengalaman hidupnya.
Lebenswelt (ditulis dengan huruf awal kapital). Berasal dari dua kata Jerman Leben
(kehidupan) dan Welt (dunia). Kata Jerman ini bisa diindonesiakan menjadi “dunia kehidupan” dan diinggriskan menjadi life-world. Lebenswelt adalah dunia kehidupan orisinal yang lepas dari teori. Itulah dunia yang dialami langsung oleh partisipan dalam penelitian fenomenologis.
Glosarium 239
life-world Lihat Lebenswelt.
lived experience Lihat pengalaman langsung.
major prosodic features Dalam lingustik, prosodic features berarti variasi-variasi yang menyertai ucapan,
seperti penekanan, tempo, atau jeda. Dalam wawancara fenomenologis, major prosodic features adalah ciri-ciri utama yang bisa diob servasi pada partisipan saat sedang menjalani sesi wawancara, seperti menangis, mata yang berkaca-kaca, mendesah, tertawa, tersenyum.
motto fenomenologis Dalam bahasa Jerman, Husserl menyerukan “Zurück zu den Sachen selbst”.
Kita bisa menginggriskannya menjadi “Back to the things themselves” atau mengindonesiakannya menjadi “Kembali ke fakta-fakta yang dialami langsung oleh partisipan”. Maksudnya, peneliti fenomenologis diminta untuk menjadikan pengalaman langsung dari partisipan sebagai fokus perhatiannya.
naratif-biografis Metode penelitian naratif yang bertujuan memahami pengalaman hidup
pribadi satu partisipan dengan menggali perjalanan hidup yang membentuk partisipan menjadi pribadi saat ini.
noema Aspek dari pengalaman, khususnya apa yang dialami. Dalam penelitian feno-
menologis, noema adalah peristiwa/kejadian/aktivitas mental yang dialami oleh partisipan. Dalam contoh “Partisipan mengalami kekerasan domestik”, keke-rasan domestik yang dialami adalah noema. Noema selalu terhubung dengan noesis.
noesis Aspek dari pengalaman, khususnya siapa yang mengalami. Dalam penelitian
fenomenologis, noesis adalah partisipan yang mengalami. Dalam contoh “Partisipan mengalami kekerasan domestik”, partisipan yang mengalami adalah noesis. Noesis selalu terhubung dengan noema.
panduan wawancara Pedoman yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam mengajukan pertanyaan-
pertanyaan penelitian. Panduan wawancara ini umumnya dibutuhkan untuk wawancara semi-terstruktur.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup240
pengalaman langsung (lived experience) Pengalaman dari orang yang mengalami langsung suatu fenomena. Pengalaman
inilah yang menjadi kerepotan peneliti fenomenologis.
penelitian fenomenologis Penelitian yang berkembang dalam psikologi yang berakar pada fenomenologi
(filsafat fenomenologis).
penelitian fenomenologis deskriptif Penelitian fenomenologis yang berakar pada fenomenologi Husserl dan
bertujuan mendeskripsikan pengalaman partisipan dengan bersandar pada epochē dan variasi imajinatif. Dalam buku ini, penelitian fenomenologis deskrip-tif disingkat menjadi PFD. Ada beberapa versi analisis data yang berkembang dalam PFD, seperti versi analisis data dari van Kaam, Giorgi, Colaizzi, atau Moustakas. Versi yang umum ditemui adalah versi Giorgi.
penelitian fenomenologis interpretatif (interpretif ) Penelitian fenomenologis yang berakar pada fenomenologi Martin Heidegger
dan bertujuan menafsirkan atau menginterpretasikan pengalaman partisipan dengan memperhatikan konteks kehidupan partisipan, seperti konteks sosial dan kultural di mana partisipan menjalani kehidupannya. Ada beberapa versi analisis dalam penelitian fenomenologis interpretatif (interpretif ), seperti versi van Manen dan versi Jonathan A. Smith. Versi yang umum ditemui adalah versi Jonathan A. Smith yang dikenal dengan nama interpretative phenomenological analysis (IPA).
perspektif orang pertama Istilah linguistis yang menunjuk pada aku/saya yang mengalami. Dalam pene-
litian fenomenologis, perspektif orang pertama adalah perspektif dari orang yang mengalami langsung suatu fenomena (peristiwa mental).
pertanyaan eksistensial Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada diri sendiri sebagai konsekuensi
dari hidup dalam situasi eksistensial. Pertanyaan-pertanyaan eksistensial adalah ekspresi dari renungan tentang kehidupan pribadi yang banyak mengalami angest (kegelisahan). Lihat juga situasi eksistensial dan angest.
pertimbangan etis Salah satu bagian dari aktivitas peneliti dalam menjaga partisipannya dari
peris tiwa yang merugikan. Salah satu wujud dari pertimbangan etis ini adalah
Glosarium 241
penandatangan consent form/informed consent (lembar persetujuan) oleh parti-sipan sebelum wawancara.
PFD Lihat penelitian fenomenologis deskriptif.
pilar IPA Tiga fondasi yang menopang yang menopang berjalannya penelitian
fenomenologis dengan IPA, yaitu (1) fenomenologi, (2) hermeneutika, dan (3) idiografi.
pilar PFD Epochē yang menjadi landasan variasi imajinatif yang pada akhirnya mengaktivasi
intuisi.
probe Pertanyaan yang diajukan peneliti untuk meminta kejelasan tentang istilah atau
ungkapan tertentu dari partisipan, misalnya “Apa yang Anda maksud dengan istilah ‘….’?”
prompt Pertanyaan yang diajukan peneliti untuk mendorong partisipan bercerita
lebih jauh tentang pengalamannya, misalnya “Tadi Anda mengatakan …. Bisa ceritakan lebih jauh tentang itu?”
rapport Dari bahasa Prancis le rapport yang bisa diindonesikan “kepercayaan” atau
diinggriskan trust. Umumnya baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris tetap menggunakan kata rapport.
rappot building Kita bisa mengindonesiakannya menjadi pembentukan kepercayaan. Rapport
building adalah upaya peneliti untuk menunjukkan kepada partisipan bahwa dia bisa dipercaya atau pantas untuk diberikan informasi tentang pengalaman hidup partisipan.
reduksi fenomenologis Proses secara bertahap mengungkapkan tema-tema pokok atau tema-tema
penting dalam analisis data. Reduksi fenomenologis dijalankan dalam keadaan epochē.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup242
reviu literatur (literature review) Peninjauan kembali literatur-literatur yang terkait atau relevan dengan topik
yang sedang diangkat.
rigor Istilah Inggris ini sebenarnya diambil utuh dari bahasa Latin ‘rigor’ yang berarti
keadaan ketat (strictness). Penelitian fenomenologis adalah penelitian yang menjalankan rigor itu sehingga disebut rigorous research. Ini berarti penelitian fenomenologis menjalankan refleksi terhadap transkrip secara ketat untuk sampai pada kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya.
rigorous terkait dengan rigor.
semboyan fenomenologis Lihat motto fenomenologis.
shared experience Pengalaman yang dimiliki bersama oleh partisipan. Dalam PFD, shared
experience itu bisa dilihat dalam konstituen atau tema pokok yang mencerminkan pengalaman seluruh partisipan.
sensitif secara psikologis Istilah Amedeo Giorgi untuk tahap analisis data dalam PFD sesudah
memunculkan unit-unit makna dari transkrip orisinal. Sensitif secara psikologis berarti peneliti menggunakan perspektif psikologisnya dalam memaknai unit-unit makna.
sikap fenomenologis Sikap yang diharapkan berkembang pada peneliti fenomenologis agar peneliti
mampu melihat esensi dari pengalaman partisipan. Sikap fenomenologis ini ditunjukkan dengan menjalankan epochē, yaitu sikap tenang dan fokus dalam melihat fenomena.
sikap natural Sikap yang menjadi kecenderungan kebanyakan orang. Fenomena masih dilihat
pada level permukaan karena masih terdistorsi dengan pandangan toretis, asumsi, penilaian, kekhawatiran, rasa senang, rasa benci, dan yang semacam itu.
Glosarium 243
situasi eksistensial Situasi riil manusia dalam menjalani hidupnya di dunia yang diwarnai angest
(Angst/anguish/angoisse/kegelisahan). Kegelisahan ini muncul secara alamiah dari kebebasan memilih jalan hidup masing-masing.
studi kasus Pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan kasus
tertentu dengan menggunakan informasi dari beragam sumber. Lihat juga kasus.
suspensi Lihat epochē.
tema Hasil pemadatan komentar atau deskripsi dalam bentuk kata atau frasa dalam
IPA. Tema bisa juga berupa kata, frasa, atau kalimat inti dalam PFD.
tema emergen Dalam IPA, tema emergen adalah hasil dari pemadatan komentar eksploratoris
dalam bentuk kata dan frasa.
tema esensial (tema invarian) Istilah dalam PFD versi Moustakas untuk tema-tema pokok yang ditemukan
dalam analisis data. Tema esensial (invarian) versi Moustakas bisa disetarakan dengan konstituen dalam versi Giorgi.
tema invarian Lihat tema esensial.
tema superordinat Istilah dalam IPA untuk hasil dari pemadatan tema-tema emergen.
tema esensial Tema yang menggambarkan inti dari pengalaman partisipan. Tema esensial
didapatkan setelah melewati proses analisis data dalam PFD. Istilah lain yang juga umum digunakan adalah konstituen.
transkrip Hasil dari proses pemindahan pernyataan lisan partisipan ke dalam bentuk
tertulis. Hasil dari transkripsi.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup244
transkripsi Proses pemindahan pernyataan lisan partisipan ke dalam bentuk tertulis.
transkreasi Proses mengalihbahasakan naskah dari satu bahasa (bahasa sumber) ke
bahasa lain (bahasa sasaran) dengan memperhatikan dan mempertimbangkan konteks dalam bahasa sasaran. Ada kebebasan dalam mengalihbahasakan, tetapi transkreator harus menjaga pesan inti dari naskah asli. Tujuannya adalah membantu pembaca dalam bahasa sasaran agar lebih mudah mengangkap pesan dari bahasa sumber.
variasi imajinatif Kadang-kadang juga ditulis variasi imajinatif bebas. Variasi imajinatif adalah
bagian dari proses analisis data di mana peneliti menggunakan “imajinasi dalam keadaan epochē ” untuk menentukan yang mutlak ada dan yang tidak mutlak ada bagi fenomena yang diteliti.
wawancara Teknik pengumpulan data dalam hampir seluruh penelitian kualitatif. Dalam
wawancara, peneliti berkomunikasi dengan partisipan tentang topik tertentu. Dalam penelitian fenomenologis, wawancara diharapkan berlangsung pasca-pembentukan rapport (kepercayaan) antara peneliti dan partisipan.
wawancara semi-struktur Bentuk wawancara yang menjadi teknik pengumpulan data utama dalam
penelitian fenomenologis.
wawancara tidak terstruktur Bentuk wawancara yang merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan
oleh peneliti-peneliti fenomenologis yang sudah berpengalaman.
Wesenschau Istilah Jerman yang berasal dari dua kata: Wesen (inti) dan schauen (melihat).
Wesenschau adalah penglihatan akan yang inti (yang esensial) dalam pengalaman partisipan dengan bantuan variasi imajinatif dan intuisi. Lihat juga intuisi.
245
Daftar Pustaka
Birtwell, B, Hammond, L, & Puckering, C. (2015). ‘Me and my bump’: An interpretative phenomenological analysis of the experiences of pregnancy for vulnerable women. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 20(2), 218–238.
Brocki, J.M. &Wearden, A.J. (2006). A critical evaluation of the use of interpretative phenomenological analysis (IPA) in health psychology. Psychology and Health, 21(1), 87–108.
Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. London: Sage.
Chenail, R.J. (2009). Making phenomenological inquiry accessible: A review of Jonathan A. Smith, Paul Flowers, and Michael Larkin’s interpretive phenomenological analysis: theory, method, and research. The weekly Qualitative Report, 2(26), 156–160.
Colaizzi, P.F. (1978). Psychological research as the phenomenologist views it. In R. S. Valle and M. King (Eds.), Existential-phenomenological alternatives for psychology. New York: Oxford University Press.
Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd edition). London: Sage.
Dalhberg, K., Dalhberg, H., &Nyström, M. (2008). Reflective lifeworld research (2nd edition). Lund: Studentlitteratur.
De Castro, A. 2003. Introduction to Giorgi’s existential phenomenological method. Psicologíadesde el Caribe, 11,45–56.
Dreher, J. (2015). Phenomenology and sociological research: The constitution of “friendship”. SocietàMutamentoPolitica, 6(12), 29–42.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup246
Englander, M. (2012). The Interview: Data collection in descriptive phenomeno-logical human scientific research. Journal of Phenomenological Psychology, 43(1), 13–35.
Fenomena. (2017). In KamusBesarBahasa Indonesia online/daring (dalamjaringan). Retrieved September 9, 2017, from https://kbbi.web.id/fenomena.
Frasa. (2017). In KamusBesarBahasa Indonesia online/daring (dalamjaringan). Retrieved September 9, 2017, from https://kbbi.web.id/frasa.
Giorgi, A. (1975a). An application of phenomenological method in psychology. In A. Giorgi, C. Fischer, & E.Murray (Eds.), Duquesne studies in phenomenological psychology: Volume II. Pittsburgh, PA: Duquesne University Press.
Giorgi, A. (1975b). Convergence and divergence of qualitative methods in psychology. In A. Giorgi, C. Fischer, & E. Murray (Eds.), Duquesne studies in phenomenological psychology: Volume 1I. Pittsburgh, PA: Duquesne University Press.
Giorgi, A. (1994). A phenomenological perspective on certain qualitative research methods. Journal of Phenomenological Psychology, 25(2), 190–220.
Giorgi. A. (2007). Concerning the phenomenological methods of husserl and heidegger and their application in psychology. Les Collectifs du CercleInterdisciplinaire de RecherchesPhénoménologiques, 1,63–78.
Giorgi, A. (2009). The descriptive phenomenological method in psychology: A modified Husserlian approach. Pittsburgh, PA: Duquesne University Press.
Giorgi, A. (2017). A response to the attempted critique of the scientific phenomenological method. Journal of Phenomenological Psychology, 48(1),83–144.
Giorgi, B.M. (2010). Application of descriptive phenomenological research method to the field of clinical research. Les Collectifs du CercleInterdisciplinaire de RecherchesPhénoménologiques, 1(éditionspéciale),119-129.
Glaser B.G. (1992) Emergence vsforcing: Basics of grounded theory. Mill Valley, CA: The Sociology Press.
Heidegger, M. (1962/1927). Being and time( J. Macquarrie& E. Robinson, Trans.).Oxford: Blackwell.
Holligan, C. (1997). Theory in initial teacher education: Students’ perspectives on its utility–a case study. British Educational Research Journal, 23(4), 533–551
Daftar Pustaka 247
Hunter, K. & Kelly, J. (2008). Grounded theory. In Knight A. & Ruddock, L. (Eds.), Advancedresearch methods in the built environment. West Sussex: Wiley-Blackwell Publishing.
Husserl, E. (1980). Ideas pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological philosophy, Third book: Phenomenology and the foundation of the sciences (T.E. Klein & W.E. Pohl, Trans.). The Hague: MartinusNijhoff.
Jung, C.G. (1968). Analytical psychology: Its theory and practice. New York: Random House.
Kata. (2017). In KamusBesarBahasa Indonesia online/daring (dalamjaringan). Retrieved September 9, 2017, from https://kbbi.web.id/kata
Langdridge, D. (2007). Phenomenological psychology: Theory, research, and method. Harlow: Pearson.
Lincoln, Y., &Guba, E. (1985). Naturalistic inquiry. California: Sage.Malinowski, B. (1984/1922). Argonauts of the western Pacific; an account of native
enterprise and adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. Illinois: Waveland Press.
Merleau-Ponty, M. (1968/1964). The visible and the invisible (A. Lingis, Trans.). Evanston, IL: Northwestern University Press.
Merrill, B. & West. L. (2009). Using biographical methods in social research. London: Sage.
Mewborn, K.N. (2005).A grounded theory study of the multicultural experiences of school psychologists (doctoral dissertation). Retrieved from http://drum.lib.umd.edu/handle/1903/2930.
Morley, J. (1998). The private theater: A phenomenological investigation of daydreaming. Journal of Phenomenological Psychology, 29(1), 116–134.
Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. London: Sage. Newshan, G. (1998). Is anybody listening? A phenomenological study of pain in
hospitalized persons with AIDS. Journal of the Association of Nurses in Aids Care, 9(2), 57–67.
Packer, M. (2011). The Science of qualitative research. New York: Cambridge University Press.
Phenomenology (philosophy). (n.d.). In Wikipedia. Retrieved September 9, 2017, from https://en.wikipedia.org/wiki/Phenomenology (philosophy).
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup248
Phenomenology (psychology). (n.d.). In Wikipedia. Retrieved September 9, 2017, from https://en.wikipedia.org/wiki/Phenomenology (psychology).
Roberts, B. (2002). Biographical research. Buckingham: Open University Press. Rogers, C.R. (1980). A way of being. Boston: Houghton Mifflin.Sartre, J-P. (1973). Unthéâtre de situations. Paris: Gallimard. Sartre, J-P. (2007). Existentialism is a humanism. (C. Macomber, Trans.). New
Haven: Yale University Press.Smith, D.W. (2013). Husserl (second edition). London: Routledge. Smith, J.A., & Osborn, M. (2003). Interpretative phenomenological analysis. In
J. A. Smith (Ed.), Qualitative psychology: A practical guide to research methods. London: Sage.
Smith, J.A., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis. London: Sage
Solomon, R.C (Ed.). (1980). Phenomenology and existentialism. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers.
Suspensi. (2017). In KamusBesarBahasa Indonesia online/daring (dalamjaringan). Retrieved September 9, 2017, from https://kbbi.web.id/suspensi
Tufford, L. & Newman, P. (2012). Bracketing in qualitative research. Qualitative Social Work 11(1), 80–96.
Valle, R.S. &Halling, S. (1989). Existential-phenomenological perspectives in psychology: Exploring the breadth of human experience. New York: Plenum Press.
Van Manen, M. (2014). Phenomenology. In Philips (Ed.),Encyclopedia of educational theory and philosophy. Sage: Thousand Oaks.
Yardley, L. (2000). Dilemmas in qualitative health research. Psychology and Health, 15(2), 215–228.
Yardley, L. (2007) Demonstrating validity in qualitative psychology. InJ. A. Smith (Ed.),Qualitative psychology: A practical guide to research methods. London: Sage.
Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and method (3rd edition). Thousand Oaks, CA: Sage.
Daftar Pustaka 251
Kot
ak 7
.1 T
rans
krip
Oris
inal
dan
Pen
cata
tan
Awa
l
Tran
skrip
oris
inal
Kom
enta
r eks
plor
ator
isTe
ma e
mer
gen
Apak
ah A
nda b
isa ce
ritak
an le
bih
jauh
ten
tang
itu?
Lebi
h jau
h te
ntan
g itu
eh …
gak
tahu
gi
man
a yah
eh …
men
urut
ku si
h itu
te
rjadi
kar
ena a
ku, a
ku, a
ku g
iman
a ya
h, ak
u ga
k ng
erti
aja k
enap
a aku
bi
sa k
ayak
gitu
wak
tu ak
u te
rima
diag
nosis
HIV
. Aku
gak
bisa
aja
berh
enti
mem
ikirk
an h
asil
diag
nosis
da
n em
… sa
ya h
arus
mele
wati
mas
a itu
dan
em r
asan
ya se
perti
har
us
belaj
ar la
gi m
enge
nal d
iriku
send
iri.
Ora
ng-o
rang
yan
g ke
nal a
ku ta
hu
kond
isiku
. Aku
cape
k ba
nget
…
bang
et …
den
gan
piki
rank
u se
ndiri
. A
ku m
engk
hawa
tirka
n pi
kira
n m
erek
a ten
tang
aku.
Men
gula
ng “e
h” “a
ku” d
an “g
ak ta
hu gi
man
a yah
?” A
paka
h ad
a kes
ulita
n m
engu
ngka
pkan
per
asaa
n? A
da h
amba
tan
dalam
men
gung
kapk
an
pera
saan
yan
g su
lit. H
amba
tan
itu je
las d
alam
peng
ulan
gan
“aku
” dan
“gak
ta
hu gi
man
a yah
”.
Ada
per
tany
aan
yang
dia
juka
n ke
diri
send
iri. M
eras
a tid
ak ta
hu k
ondi
si di
ri se
ndiri
pad
a wak
tu it
u. K
enap
a dia
bisa
beg
itu w
aktu
itu?
Ini d
ampa
k da
ri di
agno
sis.
Melu
lu m
emik
irkan
has
il di
agno
sis H
IV.
Men
galam
i mas
a krit
is. A
paka
h in
i mas
a yan
g sa
ngat
sens
itif d
alam
hi
dupn
ya? B
elajar
men
gena
l diri
? Gak
lagi
men
gena
l diri
? d
ampa
k di
agno
sis.
Apa
artin
ya o
rang
lain
? Apa
kah
ini d
ampa
k so
sial h
asil
diag
nosis
?M
eras
a let
ih. P
engu
lang
an “b
ange
t” ses
udah
“cap
ek” m
enek
anka
n ke
rja ke
ras
mem
ikirk
an so
lusi.
M
enga
ntisi
pasi
peni
laian
ora
ng la
in se
suda
h di
agno
sis. D
ampa
k di
agno
sis.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup252
Mer
eka p
asti
tahu
ada y
ang
salah
sa
ma a
ku. A
ku p
aran
oid.
Mer
eka
baka
l tah
u te
ntan
g ko
ndisi
ku. A
ku
beru
saha
men
utup
i dan
ber
usah
a ta
mpi
l sep
erti
oran
g ya
ng g
ak h
idup
de
ngan
HIV
… ta
pi g
ak m
ungk
in
kare
na se
mak
in k
amu
beru
saha
be
rhen
ti m
ikiri
n, se
mak
in se
ring
piki
ran
itu m
engg
angg
u.. Y
ah.. s
eper
ti itu
lah
Apa
kah
“salah
” ber
arti
dulu
nya b
aik
seka
rang
suda
h ga
k ba
ik? I
ni te
ntan
g pe
nam
pilan
di d
epan
ora
ng. A
paka
h “p
aran
oid”
ber
arti
taku
t aka
n kh
awat
ir or
ang
lain?
Kok
has
il m
edis
bisa
mem
beri
dam
pak
sepa
rah
ini?
Upa
ya y
ang
dian
ggap
mus
tahi
l.G
ejolak
pik
iran
dalam
diri
send
iri. A
paka
h un
gkap
an in
i men
unju
kkan
pe
rasa
an d
ipen
jara o
leh p
ikira
n se
ndiri
? Ini
dam
pak
dari
diag
nosis
.
Bisa
cerit
akan
siap
a “m
erek
a” ya
ng
Anda
mak
sud?
Hm
m..
apak
ah te
man
de
kat?
Tem
an d
ekat
, kelu
arga
, sah
abat
, sia
pa
saja,
bah
kan
oran
g ya
ng b
aru
aku
tem
ui. A
ku h
anya
mer
asa g
ak b
isa,
aku
aku
gak
bisa
mer
asa g
ak b
erda
ya
kare
na ak
u ga
k lag
i (m
ende
sah)
aku
mer
asa k
ehila
ngan
sesu
atu
yang
aku
gak
bisa
, aku
em…
aku
udah
cape
k,
Kha
watir
dala
m p
erju
mpa
an d
enga
n sia
pa sa
ja ya
ng d
item
ui. M
ulai
dar
i or
ang
yang
ken
al de
kat s
ampa
i ora
ng y
ang
kena
l sam
bil l
alu.
Ada
rasa
tida
k be
rday
a. Pe
ngul
anga
n ka
ta “a
ku” d
an “g
ak bi
sa” m
empe
rkua
t ra
sa ti
dak b
erda
ya it
u.
Men
desa
h (ra
sa se
dih?
). D
ia m
eras
a keh
ilang
an.
Dia
mer
asa s
egala
nya s
udah
mele
lahka
n.
Daftar Pustaka 253
aku
gak
bisa
, gak
ada l
agi y
ang
bisa
ak
u be
rikan
, aku
mer
asa a
ku g
ak
pant
as u
ntuk
ber
bagi
… G
iman
a ya
h? A
ku b
enar
-ben
ar sh
ocked
, sep
erti
gem
pa …
aku
gak
tahu
apak
ah ak
u ud
ah m
enjaw
ab p
erta
nyaa
nmu.
Tid
ak ad
a lag
i yan
g di
rasa
ber
arti
pada
diri
send
iri. A
da y
ang
agak
jan
ggal
dalam
uca
pan
di si
ni. D
ia m
eras
a tid
ak b
isa b
erba
gi. A
paka
h di
a du
luny
a ora
ng y
ang
sena
ng b
erba
gi?
“shock
ed”,
“sepe
rti ge
mpa
” men
unju
kkan
gunc
anga
n pe
rasa
an ya
ng lu
ar bi
asa.
Ini d
ampa
k dia
gnos
is.
Kam
u ta
di b
ilang
ada p
eras
aan
kehi
langa
n, [i
ya, i
ya] t
idak
pun
ya ar
ti [iy
a]. B
isa ce
ritak
an ap
a yan
g te
rasa
hi
lang?
Saya
han
ya m
enge
cek
ulan
g. D
ia m
enan
gis.
Suas
ana y
ang
sang
at
emos
iona
l.
Kom
enta
r: Pe
rhat
ikan
bah
wa b
ahas
a yan
g di
guna
kan
dalam
kom
enta
r eks
plor
ator
is tid
ak le
pas d
ari k
alim
at, b
ahka
n ba
gian
dar
i ka
limat
juga
dia
nalis
is, te
rmas
uk m
ajor
pro
sodic
featu
re (c
iri-c
iri y
ang
men
yerta
i uca
pan)
, sep
erti
ters
enyu
m, m
ende
sah,
dan
lain
-lain
. Pe
mer
iksa
an it
u di
lakuk
an se
cara
det
ail.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup254
Kot
ak 8
.2 P
enge
mba
ngan
Tem
a Em
erge
n
Tran
skrip
oris
inal
Kom
enta
r eks
plor
ator
isTe
ma e
mer
gen
Apak
ah A
nda b
isa ce
ritak
an le
bih
jauh
ten
tang
itu?
Lebi
h jau
h te
ntan
g itu
eh …
gak
ta
hu g
iman
a yah
eh …
men
urut
ku
sih it
u te
rjadi
kar
ena a
ku, a
ku, a
ku
gim
ana y
ah, s
aya g
ak n
gerti
aja
kena
pa ak
u bi
sa k
ayak
gitu
wak
tu
aku
terim
a dia
gnos
is H
IV. A
ku
gak
bisa
aja b
erhe
nti m
emik
irkan
ha
sil d
iagn
osis
dan
em …
saya
ha
rus m
elewa
ti m
asa i
tu d
an
em r
asan
ya se
perti
har
us b
elajar
lag
i men
gena
l diri
ku se
ndiri
. O
rang
-ora
ng y
ang
kena
l aku
tahu
ko
ndisi
ku. A
ku ca
pek
bang
et…
ba
nget
… d
enga
n pi
kira
nku
send
iri.
Aku
men
gkha
watir
kan
piki
ran
mer
eka t
enta
ng ak
u. M
erek
a Pas
ti ta
hu ad
a yan
g sa
lah sa
ma a
ku. A
ku
para
noid
. Mer
eka b
akal
tahu
tent
ang
kond
isiku
. Aku
ber
usah
a men
utup
i da
n be
rusa
ha ta
mpi
l sep
erti
oran
g ya
ng g
ak h
idup
den
gan
HIV
…
Men
gula
ng “e
h” “a
ku” d
an “g
ak ta
hu gi
man
a yah
?” A
paka
h ad
a ke
sulit
an m
engu
ngka
pkan
per
asaa
n? A
da h
amba
tan
dalam
m
engu
ngka
pkan
per
asaa
n ya
ng su
lit. H
amba
tan
itu je
las d
alam
pe
ngul
anga
n “a
ku” d
an “g
ak ta
hu gi
man
a yah
”. A
da p
erta
nyaa
n ya
ng d
iaju
kan
ke d
iri se
ndiri
. Mer
asa t
idak
tahu
ko
ndisi
diri
send
iri p
ada w
aktu
itu.
Ken
apa d
ia b
isa b
egitu
wak
tu
itu? I
ni d
ampa
k da
ri di
agno
sis.
Melu
lu m
emik
irkan
has
il di
agno
sis H
IV.
Men
galam
i mas
a krit
is. A
paka
h in
i mas
a yan
g sa
ngat
sens
itif
dalam
hid
upny
a? B
elajar
men
gena
l diri
? Gak
lagi
men
gena
l diri
?
dam
pak
diag
nosis
.A
pa ar
tinya
ora
ng la
in? A
paka
h in
i dam
pak
sosia
l has
il di
agno
sis?
Mer
asa l
etih
. Pen
gula
ngan
“ban
get”
sesud
ah “c
apek
” m
enun
jukk
an
kerja
kera
snya
mem
ikirk
an so
lusi.
M
enga
ntisi
pasi
peni
laian
ora
ng la
in se
suda
h di
agno
sis. D
ampa
k di
agno
sis.
Apa
kah
“salah
” ber
arti
dulu
nya b
aik
seka
rang
suda
h ga
k ba
ik? I
ni
tent
ang
pena
mpi
lan d
i dep
an o
rang
. Apa
kah
“par
anoi
d” b
erar
ti ta
kut a
tau
khaw
atir
oran
g lai
n? K
ok h
asil
med
is bi
sa m
embe
ri da
mpa
k se
para
h in
i?
Diri
yan
g m
em pe
r tany
a-ka
n di
ri se
ndiri
Ras
a tid
ak m
enen
tu
Piki
ran
yang
ber
ulan
g
Upa
ya m
enge
nal l
agi d
iri
send
iriR
elasi
sosia
l yan
g te
r-ga
nggu
Kele
tihan
Kek
hawa
tiran
akan
pe-
nilai
an o
rang
lain
Perh
atia
n pa
da p
enam
-pi
l an d
iriPe
nyem
buny
ian
kond
isi
diri
Piki
ran
yang
ber
ulan
g
Daftar Pustaka 255
tapi
gak
mun
gkin
kar
ena s
emak
in
kam
u be
rusa
ha b
erhe
nti m
ikiri
n,
sem
akin
serin
g pi
kira
n itu
m
engg
angg
u.. Y
ah..
sepe
rti it
ulah
Solu
si ya
ng d
iang
gap
mus
tahi
l dija
lanka
n.
Piki
ran
beru
lang
yang
sem
akin
kua
t. A
paka
h un
gkap
an in
i m
enun
jukk
an p
eras
aan
dipe
njar
a oleh
pik
iran
send
iri? I
ni d
ampa
k da
ri di
agno
sis.
Bisa
cerit
akan
siap
a “m
erek
a” ya
ng
Anda
mak
sud?
Hm
m..
apak
ah te
man
de
kat?
Tem
an d
ekat
, kelu
arga
, sah
abat
, sia
pa sa
ja, b
ahka
n or
ang
yang
bar
u ak
u te
mui
. Aku
han
ya m
eras
a ga
k bi
sa, a
ku ak
u ga
k bi
sa m
eras
a ga
k be
rday
a kar
ena a
ku g
ak la
gi
(men
desa
h) ak
u m
eras
a keh
ilang
an
sesu
atu
yang
aku
gak
bisa
, aku
em…
ak
u ud
ah ca
pek,
aku
gak
bisa
, gak
ad
a lag
i yan
g bi
sa ak
u be
rikan
, aku
m
eras
a aku
gak
pan
tas u
ntuk
ber
bagi
…
Gim
ana y
ah? A
ku b
enar
-ben
ar
shock
ed, s
eper
ti ge
mpa
… a
ku g
ak
tahu
apak
ah ak
u ud
ah m
enjaw
ab
perta
nyaa
nmu.
Kha
watir
dala
m p
erju
mpa
an d
enga
n sia
pa sa
ja ya
ng d
item
ui. M
ulai
da
ri or
ang
yang
ken
al de
kat s
ampa
i ora
ng y
ang
kena
l sam
bil l
alu.
Ada
rasa
tida
k be
rday
a. Pe
ngul
anga
n ka
ta “a
ku” d
an “g
ak bi
sa”
mem
perk
uat r
asa t
idak
berd
aya i
tu.
Men
desa
h (ra
sa se
dih?
). D
ia m
eras
a keh
ilang
an.
Dia
mer
asa s
egala
nya s
udah
mele
lahka
n.
Tid
ak ad
a lag
i yan
g di
rasa
ber
arti
pada
diri
send
iri. A
da y
ang
agak
jang
gal d
alam
uca
pan
di si
ni. D
ia m
eras
a tid
ak b
isa b
erba
gi.
Apa
kah
dia d
ulun
ya o
rang
yan
g se
nang
ber
bagi
? “sh
ocked
”, “se
perti
gem
pa” m
enun
jukk
an gu
ncan
gan
pera
saan
yang
luar
bi
asa.
Ini d
ampa
k dia
gnos
is.
Rela
si so
sial y
ang
terg
angg
uK
etid
akbe
rday
aan
Ras
a keh
ilang
an d
iri
Kele
tihan
Dep
resi?
Gun
cang
an em
osio
nal
Kam
u ta
di b
ilang
ada p
eras
aan
kehi
langa
n, [i
ya, i
ya] t
idak
pun
ya ar
ti [iy
a]. B
isa ce
ritak
an ap
a yan
g te
rasa
hi
lang?
Saya
han
ya m
enge
cek
ulan
g. D
ia m
enan
gis.
Mom
en y
ang
sang
at
emos
iona
l.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup256
Kotak 8.3 Sebaran Awal Tema Emergen
• diri yang mempertanyakan diri sendiri• rasa tidak menentu• pikiran yang berulang• upaya mengenal lagi diri sendiri • relasi sosial yang terganggu• keletihan • kekhawatiran akan penilaian orang lain• perhatian pada penampilan-diri
• penyembunyian kondisi diri• pikiran yang berulang• relasi sosial yang terganggu• ketidakberdayaan • rasa kehilangan • keletihan• depresi? • guncangan emosional
Komentar: Di sini kita bertemu dengan beberapa tema saja. Ini hanya contoh dari potongan transkrip. Jika seluruh transkrip dianalisis, kita akan bertemu dengan tema yang jumlahnya bisa mencapai ratusan. Ada saatnya tema yang berulang, tumpang tindih, dan tidak relevan dengan penelitian digugurkan sehingga yang tersisa hanya satu, seperti tema-tema yang dicoret di atas.
Daftar Pustaka 257
Kotak 11.1 Penghayatan Transkrip dan Pembentukan Unit Makna
Transkrip/Deskripsi Natural Transkrip/Deskripsi Natural
Peneliti hanya membaca seluruh transkrip
Baca sampai tuntas dan hayati
Peneliti membaca dan merasakan tekstur transkrip
Hayati transkrip dan beri tanda satuan-satuan makna
Lebih jauh tentang itu eh … gak tahu gimana yah eh… menurutku sih itu terjadi karena aku, aku, aku gimana yah, aku gak ngerti aja kenapa aku bisa begitu waktu itu saat aku terima diagnosis HIV. Aku gak bisa aja berhenti memikirkannya dan em … aku harus melewati masa itu dan em rasanya seperti harus belajar lagi mengenal diriku sendiri. Orang-orang yang kenal aku pasti tahu kondisiku. Aku capek banget… banget … capek dengan pikiranku sendiri. Aku mikirin pikiran mereka tentang aku. Mereka Pasti tahu ada yang salah sama aku. Aku paranoid. Mereka bakal tahu tentang kondisiku. Aku berusaha menutupi dan berusaha tampil seperti orang yang gak hidup dengan HIV tapi gak mungkin karena semakin kamu berusaha berhenti mikirin, semakin sering pikiran itu mengganggu.. Yah.. seperti itulah.
Lebih jauh tentang itu eh … gak tahu gimana yah eh… menurutku sih itu terjadi karena aku, aku, aku gimana yah, aku gak ngerti aja kenapa aku bisa begitu waktu itu1 saat aku terima diagnosis HIV. Aku gak bisa aja berhenti memikirkannya2 dan em … aku harus melewati masa itu dan em rasanya seperti harus belajar lagi mengenal diriku sendiri.3 Orang-orang yang kenal aku pasti tahu kondisiku. Aku capek banget… banget … dengan pikiranku sendiri. Aku mikirin pikiran mereka tentang aku. Mereka Pasti tahu ada yang salah sama aku. Aku paranoid. Mereka bakal tahu tentang kondisiku.4 Aku berusaha menutupi dan berusaha tampil seperti orang yang gak hidup dengan HIV5 tapi gak mungkin karena semakin kamu berusaha berhenti mikirin, semakin sering pikiran itu mengganggu.. Yah.. seperti itulah6
Transkrip pada kolom ini adalah bahan mentah. Jika seluruhnya sudah dibaca, pindah ke kolom kanan
Transkrip pada kolom ini adalah bahan siap olah. Jika seluruhnya sudah diberi tanda, silakan pindah ke langkah kedua
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup258
Kotak 11.2 Deskripsi untuk Unit Makna
Unit Makna Deskripsi Unit Makna
1. Lebih jauh tentang itu eh … gak tahu gimana yah eh… menurutku sih itu terjadi karena aku, aku, aku gimana yah, aku gak ngerti aja kenapa aku bisa begitu waktu itu
1. P ingin mengungkapkan apa yang terjadi padanya, tetapi tidak tahu apa yang harus dikatakan.
2. saat aku terima diagnosis HIV. Aku gak bisa aja berhenti memikirkannya
2. Sesudah mendapatkan hasil diag nosis, P memikirkan terus hasil diagnosis.
3. dan em … aku harus melewati masa itu dan em rasanya seperti harus belajar lagi mengenal diriku sendiri.
3. P melihat dirinya menjadi berbeda sehingga perlu mengenal kembali diri sendiri.
4. Orang-orang yang kenal aku pasti tahu kondisiku. Aku capek banget… banget … capek dengan pikiranku sendiri. Aku mikirin pikiran mereka tentang aku. Mereka Pasti tahu ada yang salah sama aku. Aku paranoid. Mereka bakal tahu tentang kondisiku.
4. P menjadi paranoid dengan menganggap orang-orang yang dia kenal sedang memikirkan tentang kondisinya dan dia letih sekali dengan pikirannya itu.
5. Aku berusaha menutupi dan berusaha tampil seperti orang yang gak hidup dengan HIV
5. P berusaha menampilkan diri seolah-olah tanpa masalah di depan orang lain.
6. tapi gak mungkin karena semakin kamu berusaha berhenti mikirin, semakin sering pikiran itu mengganggu.. Yah.. seperti itulah.
6. P merasa mustahil melawan pikirannya yang terus sibuk memikirkan hasil diagnosis
Daftar Pustaka 259
Kotak 11.3 Deskripsi Psikologis untuk Deskripsi Unit Makna
Unit Makna Deskripsi Unit Makna Deskripsi Psikologis
1. Lebih jauh tentang itu eh … gak tahu gimana yah eh… menurutku sih itu terjadi karena aku, aku, aku gimana yah, aku gak ngerti aja kenapa aku bisa begitu waktu itu
2. saat aku terima diagnosis HIV. Aku gak bisa aja berhenti memikirkannya
3. dan em … aku harus melewati masa itu dan em rasanya seperti ha rus belajar lagi mengenal diriku sendiri.
4. Orang-orang yang kenal aku pasti tahu kondisiku. Aku capek banget… banget … capek dengan pikiran-ku sendiri. Aku mikirin pikiran mereka tentang aku. Mereka Pasti tahu ada yang salah sama aku. Aku paranoid.
P ingin mengungkapkan apa yang terjadi padanya, tetapi tidak tahu apa yang harus dikatakan.
Sesudah mendapatkan hasil diagnosis, P memikirkan terus hasil diagnosis.
P melihat dirinya menjadi berbeda sehingga perlu mengenal kembali.
P menjadi paranoid dengan menganggap orang-orang yang dia kenal sedang memikirkan tentang kondisinya dan dia letih sekali dengan pikirannya itu.
---- (tidak relevan dan bisa disingkirkan)
P merasakan pikiran yang berulang tentang hasil diagnosis.
P mengalami perubahan persepsi-diri pasca-diagnosis dan berupaya menyesuaikan diri.
P menganggap orang-orang yang dia kenal memikirkan dia yang didiagnosis HIV.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup260
Mereka bakal tahu tentang kondisiku.
5. Aku berusaha menu tupi dan berusaha tam pil seperti orang yang gak hidup dengan HIV
6. tapi gak mungkin karena semakin kamu ber usa-ha berhenti mikirin, se makin sering pikiran itu mengganggu.. Yah.. seperti itulah.
P berusaha menampilkan diri seolah-olah tanpa masalah di depan orang lain.
merasa mustahil melawan pikirannya yang terus sibuk memikirkan hasil diagnosis
5+6: Dalam relasi sosial, P berusaha menutupi kondisinya tapi upaya itu mustahil dipertahankan.
Hasil akhirnya, kolom paling kanan yang bersih dari pernyataan yang berulang, tumpang tindih, dan tidak relevan dengan pertanyaan penelitian.
Daftar Pustaka 261
Kotak 11.4 Deskripsi Struktural untuk Deskripsi Psikologis
Deskripsi Psikologis Deskripsi Struktural
P merasakan pikiran yang berulang tentang hasil diagnosis.
P mengalami perubahan persepsi-diri pasca-diagnosis dan berupaya mende-fini si kan ulang dirinya.
P menganggap orang-orang yang dia ke nal memikirkan dia yang didiagnosis HIV.
Bagi partisipan, pengalaman didiagnosis positif HIV berdampak pada munculnya pikiran yang berulang tentang hasil diag-nosis. Hasil diagnosis itu telah meng-ubah cara partisipan melihat dirinya sen-diri dan dia berusaha menyesuaikan diri dengan dirinya yang baru. Hasil diag-nosis juga memiliki dampak sosial.
(5+6): Dalam relasi sosial, P berusaha menutupi kondisinya tapi upaya itu mustahil dipertahankan.
Partisipan merasakan munculnya pikiran paranoid bahwa orang yang menge nal-nya sedang memikirkan penyakit yang dialaminya. Partisipan berusaha menang-kal pikiran paranoid itu dengan berusaha menunjukkan bahwa tidak ada yang ber ubah dengan dirinya, tetapi upaya itu dianggap mustahil.
Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup262
Tentang Penulis
YF La Kahija adalah pengajar pada Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Sejak awal meng-ajar, dia dipercaya mengampu matakuliah metodologi penelitian kualitatif dan secara khusus mengembangkan model penelitian fenomenologis deskriptif sebagai alter-natif untuk penyelesaian skripsi maha siswa. Pada tahun 2010, La Kahija menempuh pendidikan magister di University of Northampton, Inggris, dengan mengambil spesi a li sasi di bidang psikologi transpersonal. Di sana, dia berkenalan dengan pendekatan fenomenologis yang dikembangkan oleh Jonathan A. Smith dan sudah dikenal luas dengan nama interpretative phenomenological analysis (IPA). Pada saat ini, IPA telah menjadi pendekatan kualitatif yang banyak digunakan dalam psikologi dan mempunyai representatif di banyak negara. Untuk Indonesia, Jonathan Smith menunjuk La Kahija sebagai representatif IPA.
Meski mengenal IPA, La Kahija tidak menutup diri dengan versi lain dalam pendekatan fenomenologis. Dia juga terbuka dengan penelitian fenomenologis lain, khususnya penelitian fenomenologis deskriptif yang dibentuk oleh Amedeo Giorgi di Amerika Serikat dan juga banyak digunakan dalam psikologi dan ilmu-ilmu kemanusiaan (human sciences) yang lain. La Kahija juga menjalin kontak dengan Giorgi dalam rangka penerbitan buku "Fenomenologi: Dasar-dasar Filosofis untuk Riset Fenomenologis" yang akan menjadi pendamping buku ini.
Selain tertarik dengan pendekatan fenomenologis, La Kahija juga tertarik dengan pengembangan hipnosis ilmiah yang diawali dengan penerbitan bukunya yang berjudul “Hipnoterapi: Prinsip-prinsip Dasar Praktik Psikoterapi”. Latar belakang akademisnya di bidang psikologi transpersonal juga telah mendorongnya mengembangkan terapi Eling lan Awas (ELA) yang berakar pada spiritualitas Timur.