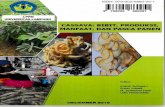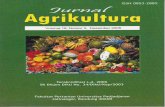PENGARUH MACAM DAN KONSENTRASI BAHAN ORGANIK SEBAGAI SUMBER ZAT PENGATUR TUMBUH ALAMI TERHADAP...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of PENGARUH MACAM DAN KONSENTRASI BAHAN ORGANIK SEBAGAI SUMBER ZAT PENGATUR TUMBUH ALAMI TERHADAP...
PENGARUH MACAM DAN KONSENTRASI BAHAN ORGANIKSEBAGAI SUMBER ZAT PENGATUR TUMBUH ALAMITERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT TEBU (Saccharum
officinarum L.)
SKRIPSI
OLEHHELENA LEOVICI
09/281768/PN/11591
FAKULTAS PERTANIAN0
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut Arifin (2008), gula merupakan salah satu
komoditas khusus di bidang pertanian yang telah
ditetapkan Indonesia dalam forum perundingan Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO), bersama dengan beras, jagung,
dan juga kedelai. Bahan baku industri gula yang merupakan
komoditas unggulan dan dibudidayakan di Indonesia yakni
tebu (Saccharum officinarum L).
Beberapa tahun terakhir industri gula mengalami
penurunan produksi hingga mencapai titik nadir sebesar
1,48 juta ton pada tahun 1999. Sementara itu pada tahun
2002 produksi gula mencapai 1,76 juta ton, sedangkan
konsumsi gula nasional mencapai 3,3 juta ton, sehingga
mencapai defisit sebesar 1,54 juta ton. Defisit yang
sangat besar tersebut dapat dicukupi oleh masuknya gula
impor dengan mudah dan harga yang kompetitif, walaupun
pendapatan petani terancam menurun karena daya saing
produk gula lokal lemah. Penurunan produktivitas selama
27 tahun (1975-2002) terutama dicerminkan
penurunan rendemen, sementara produktivitas tanaman
alternatif mengalami kenaikan. Agar tebu memiliki daya
saing terhadap tanaman alternatif, maka kinerjanya harus
ditingkatkan agar mendapatkan hasil yang mendekati
2
potensi hasil dengan penerapan baku teknis pengelolaan
usahatani dan prosesing gula (Anonim, 2008).
Ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi gula
menjadi suatu masalah yang hendaknya segera diatasi.
Beberapa upaya dapat dilakukan dengan cara melakukan
perbaikan terhadap lahan-lahan pertanaman tebu, mulai
dari bibit yang digunakan, tanah yang dipakai sebagai
media tanam, pemeliharaan, hingga penanganan pascapanen.
Produktivitas tebu dapat mencapai optimal apabila upaya
perbaikan tersebut dilakukan dengan baik. Rendemen tebu
yang dihasilkan sangat dimungkinkan akan meningkat dengan
produktivitas tebu yang optimal. Hal ini berpengaruh pada
kualitas dan kuantitas gula yang diproduksi. Selain
perbaikan pada lahan pertanaman tebu, upaya lain yang
mungkin dapat dilakukan adalah perluasan lahan.
Perluasan lahan kini tidak lagi terpaku pada lahan-
lahan subur saja karena dewasa ini lahan subur sudah
semakin sulit ditemukan akibat pertambahan penduduk yang
semakin tinggi dan kegiatan perekonomian yang memacu alih
fungsi lahan. Oleh sebab itu, kegiatan pertanian saat ini
sudah mulai dikembangkan di lahan marginal yang mempunyai
karakteristik keterbatasan dalam sesuatu hal, baik
keterbatasan satu unsur/komponen maupun lebih dari satu
unsur/komponen (Gunadi, 2002). Salah satu lahan marginal
yang mungkin dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian
ialah lahan pasir pantai.
3
Di Indonesia terdapat ± 1.060.000 ha lahan pasir
pantai. Kendala umum lahan ini bagi pertanian adalah
tekstur kasar, daya simpan air/zat hara rendah, kandungan
bahan organik rendah, kemampuan menukar kation yang
rendah, daya meluluskan air dan udara tinggi, suhu tanah
dan udara pada siang hari sangat tinggi, kecepatan angin
sangat tinggi, angin mengandung partikel garam, dan mudah
tererosi oleh angin (Kertonogero et al., 2009).
Keterbatasan lahan pasir pantai perlu diatasi supaya
mampu menjadi tempat tumbuh tanaman yang baik.
Lahan pasir pantai memungkinkan bagi tebu untuk
tumbuh dengan baik. Menurut Elawad et al. (1982), tebu
termasuk kelompok tanaman C¬4 yang memiliki sifat antara
lain dapat beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang
terik (panas) dan bersuhu tinggi, fotorespirasinya rendah
dimana sangat efisien dalam menggunakan air serta toleran
terhadap lingkungan yang mengandung garam.
Zat pengatur tumbuh (ZPT) adalah senyawa organik
bukan hara (nutrien) tetapi dapat merubah proses
fisiologis tumbuhan. Menurut Gardner et al. (1991),
seringkali pemasokan zat pengatur tumbuh secara alami itu
di bawah optimal, dan dibutuhkan sumber dari luar untuk
menghasilkan respon yang dikehendaki. Pada tahapan
pembibitan secara vegetatif (metode stek), aplikasi zat
pengatur tumbuh atau hormon tumbuh secara langsung dapat
meningkatkan kualitas bibit serta mengurangi jumlah bibit
yang pertumbuhannya abnormal. Zat pengatur tumbuh
4
memiliki potensi untuk meningkatkan persentase
keberhasilan pembibitan dan dapat mempercepat pembentukan
serta pertumbuhan akar dan tunas dari bahan stek. Terkait
dengan aplikasi ZPT eksternal untuk penyetekan, beberapa
faktor seperti macam dan konsentrasi perlu diperhatikan.
Penggunaan tidak boleh sembarangan karena penggunaan ZPT
eksternal yang berlebihan justru dapat menghambat
pertumbuhan.
Berdasarkan sumbernya, ZPT dapat diperoleh baik
secara alami maupun sintetik. Zat pengatur tumbuh alami
umumnya langsung tersedia di alam dan berasal dari bahan
organik, contohnya air kelapa, urin sapi, dan ekstraksi
dari bagian tanaman. Zat pengatur tumbuh sintetik didapat
melalui proses sintesa oleh manusia dan sudah dapat
dipastikan rumus kimianya (Shahab et al., 2009; Zhao, 2010).
Zat pengatur tumbuh bersumber bahan organik lebih
bersifat ramah lingkungan, mudah didapat, aman digunakan,
dan lebih murah.
Aplikasi bahan organik sebagai sumber ZPT alami
diharapkan dapat mempercepat pembentukan serta
pertumbuhan akar dan tajuk bibit tebu di media pasir
pantai. Selain itu, dapat menunjukkan pula macam dan
konsentrasi bahan organik yang paling optimum sebagai
sumber ZPT alami bagi pertumbuhan bibit tebu. Hal ini
dapat dijadikan sebagai rujukan bagi usahatani ataupun
perkebunan tebu supaya dalam melakukan pembibitan dapat
lebih efektif, efisien, aman, dan ramah lingkungan.
5
B. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui pengaruh macam dan konsentrasi bahan
organik sebagai sumber zat pengatur tumbuh alami
terhadap pertumbuhan bibit tebu.
2. Menentukan konsentrasi optimum beberapa macam bahan
organik sebagai sumber zat pengatur tumbuh alami bagi
pertumbuhan bibit tebu.
C. Kegunaan
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan
pemanfaatan bahan organik sebagai sumber zat pengatur
tumbuh yang bermanfaat bagi pertumbuhan tebu.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan
bagi usahatani ataupun perkebunan tebu supaya dalam
melakukan pembibitan dapat lebih efektif, efisien,
aman, dan ramah lingkungan.
6
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tebu (Saccharum officinarum L.)
Tebu merupakan tanaman yang berasal dari India.
Namun, banyak juga literatur yang menyatakan bahwa tebu
berasal dari Polynesia. Meski demikian, menurut Nikolai
Ivanovich Vavilov, seorang ahli botani Soviet, yang telah
melakukan ekspedisi pada 1887-1942 ke beberapa daerah di
Asia, Eropa, Afrika, Amerika Selatan, dan seluruh Uni
Soviet, memastikan bahwa sentrum utama asal tanaman ini
adalah India dan Indo-Malaya yang meliputi Indo-China,
Malaysia, Philipina, dan Indonesia (Ahira, 2009).
Berikut merupakan klasifikasi botani tanamaan tebu
(Plantamor, 2012):
Kingdom : Plantae (tumbuhan)
Subkingdom : Tracheobionta (tumbuhan
berpembuluh)
Super Divisi : Spermatophyta
(menghasilkan biji)
Divisi : Magnoliophyta (tumbuhan berbunga)
Kelas : Liliopsida (berkeping satu/monokotil)
Sub Kelas : Commelinidae
Ordo : Poales
Famili : Poaceae (suku rumput-rumputan)
Genus : Saccharum
Spesies : Saccharum officinarum L.
7
Tanaman tebu memiliki morfologi yang tidak jauh
berbeda dengan tumbuhan yang berasal dari famili rumput-
rumputan. Tanaman ini memiliki ketinggian sekitar 2-5
meter. Menurut Nadia (2012), morfologi tanaman tebu
secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian,
yaitu:
a. Akar: berbentuk serabut, tebal dan berwarna putih
b. Batang: berbentuk ruas-ruas yang dibatasi oleh
buku-buku, penampang melintang agak pipih, berwarna
hijau kekuningan
c. Daun: berbentuk pelepah, panjang 1-2 m, lebar 4-8
cm, permukaan kasar dan berbulu, berwarna hijau
kekuningan hingga hijau tua
d. Bunga: berbentuk bunga majemuk, panjang sekitar
30 cm.
Pada bagian pangkal sampai pertengahan batang
memiliki ruas yang panjang, sedangkan pada bagian pucuk
memiliki ruas yang pendek. Pada bagian pucuk batang
terdapat titik tumbuh terdapat titik tumbuh yang penting
untuk pertumbuhan meninggi. Selain itu juga terdapat
lapisan berlilin di bagian bawah ruas dan pada ruas di
bagian pucuk batang. Daun tanaman tebu merupakan jenis
daun tidak lengkap, karena terdiri dari helai daun dan
pelepah daun saja. Sendi segitiga terdapat di antara
pelepah daun dan helaian daun. Pada bagian sisi dalamnya,
terdapat lidah daun yang membatasi antara helaian daun
dan pelepah daun. dalamnya terdapat lidah daun yang
8
membatasi helaian dan pelepah daun. Warna daun tebu
bermacam-macam ada yang hijau tua, hijau kekuningan,
merah keunguan dan lain-lain. Ujung daun tebu meruncing
dan tepinya bergerigi. Bunga tebu merupakan malai yang
berbentuk piramida yang terdiri dari 3 helai daun tajuk
bunga, 1 bakal buah, dan 3 benang sari. Kepala putiknya
berbentuk bulu (Putri et al., 2010).
Menurut James (2004), tanaman tebu memiliki perakaran
serabut, yang dapat dibedakan menjadi akar primer dan
akar sekundar. Akar primer adalah akar yang tumbuh dari
mata akar buku tunas stek batang bibit. Karakteristik
akar primer yaitu halus dan bercabang banyak, sedangkan
akar sekunder adalah akar yang tumbuh dari mata akar
dalam buku tunas yang tumbuh dari stek bibit, bentuknya
lebih besar, lunak, dan sedikit bercabang.
Tebu merupakan tanaman asli tropika basah. Tanaman
ini tumbuh baik di daerah beriklim tropis. Umur tanaman
sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai kurang lebih 1
tahun. Tebu tergolong tanaman perkebunan semusim yang
memiliki zat gula di dalam batangnya (Supriyadi, 1992).
Tebu juga termasuk kelompok tanaman C¬4 yang memiliki
sifat antara lain dapat beradaptasi terhadap kondisi
lingkungan yang terik (panas) dan bersuhu tinggi,
fotorespirasinya rendah dimana sangat efisien dalam
menggunakan air serta toleran terhadap lingkungan yang
mengandung garam (Elawad et al., 1982).
9
Suhu udara minimum yang diperlukan untuk pertumbuhan
tanaman tebu adalah 24 °C dan maksimum adalah 34 °C,
sedangkan suhu optimum adalah 30 °C. Pertumbuhan tanaman
akan terhenti apabila suhu dibawah 15 °C. Sinar matahari
yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ditentukan oleh
lamanya penyinaran dan intensitas penyinaran. Tanaman
tebu merupakan tanaman tropik yang membutuhkan penyinaran
12-14 jam tiap harinya. Angin dengan kecepatan kurang
lebih 10 km/jam di siang hari berdampak positif bagi
pertumbuhan tebu. Kelembaban yang rendah (45-65 %) sangat
baik untuk pemasakan karena tebu sangat cepat kering.
Kelembaban tinggi dapat mempengaruhi fotosintesis dengan
akibat pembentukan gula juga terlambat. Tanaman tebu
memerlukan curah hujan yang berkisar antara 1.000-1.300
mm/tahun dengan sekurang-kurangnya 3 bulan kering. Curah
hujan yang ideal adalah selama 5-6 bulan dengan rata-rata
curah hujan 200 mm, curah hujan yang tinggi diperlukan
untuk pertumbuhan vegetatif yang meliputi perkembangan
anakan, tinggi dan besar batang. Periode selanjutnya
selama 2 bulan dengan curah hujan 125 mm dan 4-5 bulan
berkaitan dengan curah hujan kurang dari 75 mm/bulan yang
merupakan periode kering. Pada periode ini merupakan
pertumbuhan generatif dan pemasakan tebu (Kuntohartono,
1982). Menurut Soepardiman (1996), bila musim kering tiba
sebelum pertumbuhan vegetatif berakhir, maka tanaman tebu
yang tidak diairi akan mati sebelum mencapai tingkat
masak, sebaliknya bila hujan turun terus-menerus maka
10
pertumbuhan vegetatif tebu tetap giat, sehingga tidak
mencapai kadar gula tertinggi.
Menurut Sudiatso (1999), tebu menghendaki tanah yang
gembur sehingga aerasi udara dan perakaran berkembang
sempurna. Tekstur tanah ringan sampai agak berat dengan
berkemampuan menahan air cukup dan porositas 30 %
merupakan tekstur tanah yang ideal bagi pertumbumbuhan
tanaman tebu. Kedalaman (solum) tanah untuk pertumbuhan
tanaman tebu minimal 50 cm dengan tidak ada lapisan kedap
air dan permukaan air 40 cm. Tanaman ini membutuhkan
banyak nutrisi dan memerlukan tanah subur. Tanaman tebu
juga mampu tumbuh di pantai sampai dataran tinggi antara
0-1.400 m di atas permukaan laut, tetapi mulai ketinggian
1.200 m di atas permukaan laut pertumbuhan tanaman
relatif lambat. Bentuk lahan sebaiknya bergelombang
antara 0-15 %. Lahan terbaik bagi tanaman tebu di lahan
tegalan adalah lahan dengan kemiringan kurang dari 8 %,
kemiringan sampai 10 % dapat juga digunakan untuk areal
yang dilokalisir. Syarat lahan tebu adalah berlereng
panjang, rata dan melandai sampai 2 % apabila tanahnya
ringan dan sampai 5 % apabila tanahnya lebih berat.
Sutardjo (2002) menyatakan bahwa tebu dapat ditanam
pada tanah dengan kisaran pH 5,5-7,0. Pada pH di bawah
5,5 dapat menyebabkan perakaran tanaman tidak dapat
menyerap air, sedangkan apabila tebu ditanam pada tanah
dengan pH di atas 7 tanaman akan sering kekurangan unsur
fosfor. Menurut Kuntohartono (1982), tanah dengan
11
kapasitas penukaran kation yang tinggi dapat memberikan
hara yang baik. Pada pH netral efisiensi pemupukan NPK
lebih tinggi, sedangkan pada pH kurang dari 5 dapat
menyebabkan tersedianya unsur P untuk Al dan Fe. Unsur
Cl, Fe, dan Al merupakan bahan racun utama dalam tanah.
Tanah yang airnya buruk dapat menimbulkan keracunan Fe,
Al, dan sulfat (SO4-). Kadar Cl 0,06-0,10 % telah
bersifat racun bagi akar tanaman. Keracunan unsur Fe dan
Al dapat dikurangi dengan bantuan kapur fiksasi. Oleh
karena itu, tanah masam dengan pH di bawah 5 perlu
diberikan kapur fiksasi (CaCO3). B. Zat Pengatur Tumbuh
Hormon tumbuhan atau fitohormon sering dikenal dengan
sebutan zat pengatur tumbuh (plant growth regulator) untuk
membedakanya dengan hormon pada hewan. Ada lima kelompok
utama ZPT yaitu auksin (auxins), sitokinin (cytokinins),
giberelin (gibberellins, GAs), etilena (etena, ETH), dan
asam absisat (abscisic acid, ABA). Auksin, sitokinin, dan
giberelin termasuk hormon yang bersifat positif bagi
pertumbuhan tanaman pada konsentrasi fisiologis. Etilena
dapat mendukung maupun menghambat pertumbuhan. Asam
absisat merupakan penghambat (inhibitor) pertumbuhan (Dinas
Pertanian dan Tanaman Pangan, 2012).
Zat pengatur tumbuh sangat memengaruhi pertumbuhan
suatu tanaman. Zat pengatur tumbuh berbeda dengan pupuk
karena sama sekali tidak memberikan hara kepada tanaman.
12
Zat pengatur tumbuh dalam kadar sangat kecil dapat
mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan,
perkembangan, dan atau pergerakan tumbuhan. Menurut
Djamal (2012), pertumbuhan tanaman ditentukan oleh
pupuknya, sementara arah dan kualitas dari pertumbuhan
dan perkembangan sangat ditentukan oleh hormon atau zat
pengatur tumbuh. Pemberian hormon yang tepat, baik
komposisi dan konsentrasinya, dapat mengarahkan
pertumbuhan dan perkembangan tanaman apapun. Kusumo
(1984) menambahkan bahwa tanggapan tanaman terhadap
pemberian zat pengatur tumbuh sangat bervariasi
tergantung pada fase perkembangan tumbuhan, konsentrasi
zat pengatur tumbuh yang diberikan, dan umur tanaman.
Pada dasarnya ZPT dihasilkan oleh tanaman secara alami.
Bahan ini mampu mengurangi hambatan biologis yang
terdapat dalam tanaman, sehingga penggunaannya sering
dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman.
Berdasarkan keberadaannya pada tanaman, ZPT
digolongkan menjadi ZPT endogen dan ZPT eksogen. Zat
pengatur tumbuh endogen merupakan ZPT yang diproduksi di
dalam tubuh tanaman, sedangkan zat pengatur tumbuh
eksogen adalah ZPT yang ditambahkan/diaplikasikan pada
tanaman. Dalam penyetekan, keberadaan keduanya penting
untuk diperhatikan. Jika di dalam bahan setek sudah cukup
terdapat ZPT endogen, maka penambahan ZPT eksogen tidak
diperlukan. Sebaliknya, jika bahan setek berada dalam
kondisi kurang ZPT endogen, maka keberhasilan penyetekan
13
sangat ditentukan oleh penambahan ZPT eksogen (Harsanto,
1997).
Zat pengatur tumbuh eksogen dapat berupa ZPT alami
atau ZPT sintetis. Zat pengatur tumbuh alami merupakan
ZPT yang langsung tersedia di alam dan biasanya banyak
terdapat di sekitar kita dengan harga yang murah,
contohnya: air kelapa, urin sapi, ekstraksi dari bagian
tanaman, dan lain-lain. Zat pengatur tumbuh sintetis
merupakan ZPT tiruan yang disintesa oleh manusia dan
sudah dapat dipastikan rumus kimianya. Keuntungan dari
penggunaan ZPT sintetis adalah kemudahan penggunaan dalam
dosis yang tepat, tetapi biasanya tersedia dengan harga
yang mahal. Kelemahan dari ZPT alami adalah kondisinya
yang bervariasi akibat pengaruh lingkungan maupun
fisiologis mahluk hidup yang memproduksinya. Hal yang
penting diperhatikan dalam penggunaan ZPT alami yaitu
ketepatan kondisi dan dosis yang dipakai. Meskipun
demikian, usaha ini akan memberikan kemudahan introduksi
pada petani-petani kecil karena aplikasinya tidak
membutuhkan biaya besar. Apabila bahan-bahan asli (alami)
maupun tiruannya diberikan pada tanaman, maka tanaman
akan menerima pengaruhnya sebagaimana pengaruh dari zat
pengaruh tumbuh sejenis yang dihasilkan oleh tanaman itu
sendiri (Harsanto, 1997; Prayoga, 2013).
C. Bahan Organik sebagai Sumber Zat Pengatur Tumbuh
a. Air Kelapa
14
Pada umumnya, buah kelapa yang masih muda berisi
air kelapa sekitar setengah liter. Jumlah air kelapa
semakin berkurang seiring dengan pertambahan umur buah.
Air kelapa mengandung karbohidrat, lemak, protein,
vitamin, dan sejumlah bahan anorganik yang dapat
dimanfaatkan untuk berbagai keperluan (Grimwood, 1975).
Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh
Dwidjoseputro (1989) menunjukkan bahwa selain
mengandung kalori, protein, dan mineral, air kelapa
muda mengandung sitokinin yaitu zat pengatur tumbuh
yang mempercepat pembelahan sel. Sitokinin berpengaruh
pada pertumbuhan tunas-tunas dan akar.
Air kelapa merupakan salah satu sumber alami hormon
tumbuh yang dapat digunakan untuk memacu pembelahan sel
dan merangsang pertumbuhan tanaman. Endosperm cair buah
kelapa yang belum matang mengandung senyawa yang dapat
memacu sitokinesis (Salisbury dan Ross, 1995). Air
kelapa mengandung zeatin yang termasuk kelompok
sitokinin (Taiz dan Zeiger, 1998). Sama halnya seperti
yang dinyatakan oleh George dan Sherington (1984) yaitu
bahwa zat pengatur tumbuh utama yang terdapat dalam air
kelapa adalah sitokinin. Menurut Salisbury dan Ross
(1995), sitokinin yang terdapat dalam air kelapa
terbukti mampu mendorong pembelahan sel pada jaringan
akar wortel.
Tabel 2.1. Kandungan zat yang terdapat dalam air kelapamudaKandungan Air Kelapa Muda mg/l
15
IAAKinetinZeatinGA3
GA5
GA7
0,240,440,250,460,260,05
Vitamin CRiboflavinVitamin B5InositolBiotinPiridoksinThiaminNPKMgFeNaZnCaSukrosa
mg/100 ml8,590,260,602,30
20,520,030,02
43,0013,1714,119,110,25
21,071,05
24,674,89
Sumber: Savitri (2005); Kristina dan Syahid (2012)
Menurut Abidin (1998), sitokinin dapat memacu
terjadinya organogenesis yang dapat mempercepat
pertumbuhan daun. Selain berfungsi sebagai diferensiasi
tunas adventif dan organ, juga berfungsi dalam sintesis
protein dan pembelahan sel. Dengan adanya sitokinin
maka bobot basah tanaman semakin bertambah. Hormon
auksin berfungsi untuk merangsang pembesaran sel,
sintesis DNA kromosom, serta pertumbuhan aksis
longitudinal dan juga untuk merangsang pertumbuhan akar
pada setekan atau cangkokan. Giberelin atau sering
disebut asam giberelat (GA) merupakan hormon perangsang
16
pertumbuhan tanaman yang diperoleh dari Gibberella
fujikuroi, aplikasi untuk memicu munculnya bunga.
Penelitian Murniati dan Zuhri (2002) mengungkapkan
bahwa giberelin mampu mempercepat pertumbuhan biji
kopi. Giberelin merupakan senyawa organik yang berperan
dalam proses perkecambahan karena dapat mengaktifkan
reaksi enzimatik di dalam benih (Wilkins, 1989).
Air kelapa mempunyai aktivitas sitokinin yang
tinggi dengan kehadiran dari zeatin, zeatin glukosida,
ribosida, dan 1,3-difenilurea (Wattimena et al., 2003).
Sitokinin memperlambat proses penghancuran butir-butir
klorofil pada daun-daun yang terlepas pada tanaman dan
memperlambat proses senesen pada daun, buah, dan organ-
organ lainnya (Wattimena, 1988). Selain itu, air kelapa
juga mengandung IAA (Mandang, 1993) yang mempengaruhi
pembesaran sel, mencegah absisi (pengguguran daun),
pertumbuhan akar yaitu mendorong pembesaran sel-sel
akar, dimana selang konsentrasi yang mendorong
pembesaran sel-sel akar adalah sangat rendah
(Wattimena, 1988).
Hasil penelitian Katuuk (2000) menyatakan bahwa
pemberian 250 ml/l air kelapa menunjukkan waktu yang
paling cepat dalam perkecambahan biji anggrek macan
(Grammatohyllum scriptum). Air kelapa sebagai zat pengatur
tumbuh juga telah diteliti oleh Zamroni dan Darini
(2009) untuk melihat pengaruhnya pada tanaman cabe
jamu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan
17
air kelapa 25 % berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan
setek tanaman cabe jamu.
b. Urin Sapi
Urin berasal dari metabolisme nitrogen dalam tubuh
(urea, asam urat, dan kreatin) serta 90 % terdiri dari
air. Urin yang dihasilkan ternak dipengaruhi oleh
makanan, aktivitas ternak, suhu eksternal, konsumsi
air, musim, dan lain sebagainya. Banyaknya urin dan
feses yang dihasilkan adalah sebesar 10 % dari berat
ternak. Besarnya rasio urin dan feses yang dihasilkan
oleh sapi perah yaitu 1:2,2 (31 % urin, 69 % feses)
(Taiganides, 1978). Menurut Sauer et al. (1999), sekitar
60-90 % nutrien yang dimakan ternak akan dieksresikan
kembali melalui feses dan urin. Di dalam urin, unsur
hara yang paling dominan adalah K, N, dan NH4-N. Urin
sapi berpotensi menjadi produk yang lebih bernilai
tinggi. Urin memiliki keunggulan yaitu mengandung kadar
N dan K sangat tinggi, mudah diserap tanaman dan
mengandung hormon pertumbuhan tanaman.
Menurut Dukes (1955), rata-rata jumlah urin yang
dihasilkan sapi per hari sebanyak 14,2 liter. Urin yang
normal mengandung air, urea, kraetinin, purin (asam
urat, kantin, hipoksantin), allantion, asam hipurik,
ammonia, asam amino, sulfat, sulfur, garam anorganik,
pigmen urokrom, dan urobilin. Menurut Danarto (2008),
urin sapi perah mengandung hormon yang bisa memacu
18
pertumbuhan tanaman, seperti giberelin, sitokinin, dan
auksin. Sapi perah memakan lebih banyak hijauan
daripada sapi potong sehingga kandungan auksin hijauan
dapat disekresikan lewat urin. Menurut Prawoto dan
Suprijadji (1992), ternak yang banyak makan rumput
serta hijauan lainnya mengeluarkan air seni yang
cenderung banyak mengandung auksin dan GA. Kadar auksin
urin sapi betina lebih tinggi daripada sapi jantan
(Supriadji, 1985).
Abdian dan Muniarti (2007) mengatakan bahwa urin
sapi mengandung hormon dari golongan auksin (IAA),
giberelin (GA), dan sitokinin. Fungsi utama auksin
adalah mempengaruhi pertambahan panjang batang,
pertumbuhan, diferensiasi, percabangan akar,
perkembangan buah, dominansi apikal, fototropisme, dan
geotropisme. Fungsi auksin yang paling menonjol adalah
meningkatkan pembesaran sel (Widyastuti dan
Tjokrokusumo, 2007). Auksin berkapasitas tinggi untuk
mempengaruhi pertumbuhan. Hal ini terbukti dari
beberapa penelitian yang menyimpulkan bahwa auksin
memiliki peranan penting dalam mengatur struktur dan
fungsi organ tanaman (William et al., 2006). Menurut Kevin
et al. (2007), berbagai jaringan pada tanaman memiliki
respon yang berbeda terhadap auksin.
Tabel 2.2. Kandungan zat yang terdapat dalam urin sapi perah
Kandungan Urin Sapi %19
PerahN 1,00P 0,20K 1,35H20 92,00
mg/lIAAGAN-totalP-totalKMgNH4-NNO3-N
1852,0291,09195,0181,07815,089,6
7428,00,2
pH 8,9Sumber: Sutejo (1994); Sauer et al.
(1999); Prawoto dan Suprijadji(1992)
c. Ekstrak Kecambah Kacang Hijau
Kecambah memiliki bagian putih dengan panjang
hingga tiga sentimeter. Kecambah berasal dari biji-
bijian, seperti kacang hijau. Kacang hijau termasuk
dalam famili Leguminoceae, sub famili Papilonaceae. Bentuk
kecambah diperolah setelah biji diproses selama
beberapa hari. Menurut Soeprapto (1992), komponen air
pada kecambah kacang hijau (tauge) merupakan bagian
yang terbesar bila dibandingkan dengan komponen
lainnya. Gula kacang hijau didapatkan dalam bentuk
sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Asam amino esensial
yang terkandung dalam protein kacang hijau antara lain
triptofan 1,35 %, treonin 4,50 %, fenilalanin 7,07 %,
metionin 0,84 %, lisin 7,94 %, leusin 12,90 %,
20
isoleusin 6,95 %, valin 6,25 %. Selain itu, terdapat
pula sistein, tirosin, arginin, histidin, alanin,
glisin, prolin, serta serin. Menurut Rismunandar
(1992), triptofan merupakan bahan baku sintesis IAA.
Kecambah kacang hijau (tauge) mengandung vitamin
dalam jumlah yang bermakna. Vitamin tersebut antara
lain vitamin C, thiamin, riboflavin, niasin, asam
pantothenic, vitamin B6, folat, kolin, β-karoten,
vitamin A, vitamin E (α-tokoferol), dan vitamin
K. Mineral yang ditemukan dalam jumlah bermakna dalam
tauge adalah kalsium (Ca), besi (Fe), magnesium (Mg),
fosfor (P), potasium (K), sodium (Na), zinc (Zn),
tembaga (Cu), mangan (Mn), dan selenium (Se). Ada pula
kandungan beberapa antioksidan dan zat yang berhubungan
dengan antioksidan. Kadar terbanyak dari kandungan
tersebut dalam tauge adalah fitosterol dan vitamin E,
walaupun fenol dan beberapa mineral (selenium, mangan,
tembaga, zinc, dan besi) juga memiliki jumlah yang
cukup bermakna (Amilah dan Astuti, 2006; USDA, 2009;
Astawan, 2005).
Tabel 2.3. Kandungan zat yang terdapat dalam kecambah kacang hijau
Kandungan Kecambah KacangHijau
mg/100 g
FosforKalsiumBesiVitamin B1Vitamin CFitosterolVitamin E
69,0029,000,800,07
15,0023,0015,30
21
ProteinLemakAirTriptofanTreoninFenilalaninMetioninLisinLeusinIsoleusinValin
%2,900,20
92,401,354,507,070,847,94
12,906,956,25
Sumber: Direktorat Gizi Departemen Kesehatandalam Amilah dan Astuti (2006)
Menurut Sandra (2011), ekstraksi senyawa bioaktif
dapat dilakukan pada kecambah kacang hijau yang
mengandung auksin. Penelitian yang dilakukan Mahanani
(2003) membuktikan bahwa pemberian ekstrak kecambah
kacang hijau pada tanaman kentang varietas granola yang
diberikan dua kali menunjukkan pertumbuhan dan hasil
yang terbaik dibandingkan dengan zat pengatur tumbuh
alami lain atau tanpa zat pengatur tumbuh. Perlakuan
frekuensi pemberian yang terbaik adalah dua kali, yaitu
pada 24 hst dan 31 hst.
Lakitan (1995) menyatakan bahwa giberelin banyak
terdapat pada organ tanaman yang masih muda seperti
akar, daun, biji, dan kecambah. Giberelin yang berasal
dari organ tanaman ini dapat digunakan sebagai
giberelin eksogen untuk mengoptimalkan giberelin
endogen dan ini merupakan ZPT alternatif yang mudah
didapat, aman dipakai, dan efektif. Hal ini dibuktikan
22
oleh Gardner et al. (1991) bahwa tanaman yang
diperlakukan dengan bahan yang diekstrak dari biji
kacang-kacangan tumbuhnya lebih tinggi dari tanaman
yang tidak diperlakukan. Penelitian yang dilakukan oleh
Murniati et al. (2007) juga menunjukkan bahwa perlakuan
ekstrak kecambah kacang hijau dapat meningkatkan tinggi
bibit nanas sebesar 71,45 % dan berat bibit sebesar
33,93 % dibandingkan dengan perlakuan giberelin
sintetik (GA3).
E. Hipotesis
Air kelapa muda dengan konsentrasi 25 % sebagai
sumber zat pengatur tumbuh alamiah memiliki kemampuan
lebih baik dalam memacu pertumbuhan bibit tebu jika
dibandingkan dengan urin sapi maupun ekstrak kecambah
kacang hijau.
23
III. METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2012 –
April 2013 di Kebun Tridharma milik Jurusan Budidaya
Pertanian Fakultas Pertanian UGM, Banguntapan, Bantul, D.
I. Yogyakarta.
B. Bahan dan Alat
Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu
klon tebu varietas Kidang Kencana yang berasal dari PT
Madubaru, tanah pasir dari daerah pantai selatan
Yogyakarta, pupuk urea, SP-36, KCl, air murni, air kelapa
(mengandung sitokinin, auksin, dan giberelin organik),
urin sapi (mengandung sitokinin, auksin, dan giberelin
organik), ekstrak kecambah (mengandung auksin dan
giberelin organik), dan kompos. Secara spesifik, air
kelapa yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh
dari buah kelapa yang masih muda (“degan”), urin sapi
diperoleh dari jenis sapi perah, dan ekstrak kecambah
diperoleh dari jenis kecambah kacang hijau (Vigna radiata).
Alat yang diperlukan yakni polibag ukuran
45 cm x 45 cm, penggaris atau meteran, gelas ukur,
gembor, timbangan, kantong plastik, gunting, luxmeter,
thermo-hygrometer, oven, alat-alat pertanian seperti cangkul
dan alat bantu lainnya, serta alat tulis.
24
C. Rancangan Percobaan
Penelitian ini disusun dalam Rancangan Acak Kelompok
Lengkap (RAKL) satu faktor dengan 5 blok sebagai ulangan.
Beberapa perlakuan yang terdapat dalam percobaan ini
antara lain perlakuan air kelapa muda 25 % (Z1), air
kelapa muda 50 % (Z2), air kelapa muda 75 % (Z3),
urin sapi perah 25 % (Z4), urin sapi perah 50 % (Z5),
urin sapi perah 75 % (Z6), ekstrak kecambah kacang hijau
25 % (Z7), ekstrak kecambah kacang hijau 50 % (Z8),
ekstrak kecambah kacang hijau 75 % (Z9), dan
kontrol/tanpa bahan organik (Z0) sebagai pembanding.
Pengambilan tanaman korban dilakukan sebanyak 3 kali, di
luar itu adalah tanaman sampel yang diamati setiap
minggu. Jadi, jumlah unit percobaan adalah 10 x 5 x 4 =
200 tanaman.
D. Tata Laksana Penelitian
1. Persiapan media tanam
Media tanam yang digunakan berupa tanah pasir pantai
yang diambil dari salah satu pantai di daerah selatan
Yogyakarta. Pada tahap ini media pasir pantai dicampur
kompos dengan takaran 20 ton/ha kompos. Kemudian
campuran tersebut dimasukkan ke dalam polibag dengan
volume yang sama. Polibag yang berisi media tanam
tersebut kemudian diletakkan dan ditata di lahan sesuai
dengan rancangan percobaan yang digunakan.
2. Persiapan bahan tanam25
Bahan tanam yang digunakan berupa budset dengan panjang
± 3 cm dan satu mata tunas.
3. Persiapan larutan bahan organik sebagai sumber ZPT
alami
Larutan bahan organik sebagai sumber ZPT alami
disiapkan dengan prosedur sebagai berikut: 1) larutan
air kelapa 25 % dibuat dengan melarutkan 250 ml air
kelapa ke dalam akuades hingga volume total larutan
menjadi 1 l, 2) larutan air kelapa 50 % dibuat dengan
melarutkan 500 ml air kelapa ke dalam akuades hingga
volume total larutan menjadi 1 l, 3) larutan air kelapa
75 % dibuat dengan melarutkan 750 ml air kelapa ke
dalam akuades hingga volume total larutan menjadi 1 l,
4) larutan urin sapi 25 % dibuat dengan melarutkan 250
ml urin sapi ke dalam akuades hingga volume total
larutan menjadi 1 l, 5) larutan urin sapi 50 %
dibuat dengan melarutkan 500 ml urin sapi ke dalam
akuades hingga volume total larutan menjadi 1 l, 6)
larutan urin sapi 75 % dibuat dengan melarutkan 750
ml air kelapa ke dalam akuades hingga volume total
larutan menjadi 1 l, 7) larutan ekstrak kecambah
kacang hijau 25 % dibuat dengan melarutkan 250 ml
ekstrak kecambah kacang hijau ke dalam akuades hingga
volume total larutan menjadi 1 l, 8) larutan ekstrak
kecambah kacang hijau 50 % dibuat dengan melarutkan 500
ml ekstrak kecambah kacang hijau ke dalam akuades
hingga volume total larutan menjadi 1 l, dan 9) larutan
26
ekstrak kecambah kacang hijau 75 % dibuat dengan
melarutkan 750 ml ekstrak kecambah kacang hijau ke
dalam akuades hingga volume total larutan menjadi 1 l,
dan 10) air murni 100 % (tanpa bahan organik) digunakan
untuk perlakuan kontrol.
4. Aplikasi bahan organik sebelum tanam
Sebelum ditanam, masing-masing bahan tanam (sesuai
dengan perlakuannya) terlebih dahulu direndam selama 2
jam dalam larutan bahan organik yang telah disediakan
sebagai sumber ZPT alami dan telah dicampur dithane.
5. Pemupukan
Pemupukan dasar dilakukan sebelum penanaman bibit.
Takaran pupuk yang diberikan adalah Urea 300 kg/ha, SP-
36 300 kg/ha, dan KCl 200 kg/ha. Pemupukan susulan
dilaksanakan pada umur 60 hari setelah tanam (hst)
dengan dosis pupuk Urea 200 kg/ha.
6. Penanaman
Bahan tanam berupa budset ditanam pada media pasir
pantai di polibag sesuai perlakuan dengan kedalaman ± 5
cm. Masing-masing polibag ditanami 1 bahan tanam (1
mata tunas). Kemudian dilakukan penyiraman hingga
kapasitas lapangan.
7. Penyiraman
Penyiraman dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan
tanaman. Penyiraman dilakukan sampai kapasitas
lapangan.
27
8. Aplikasi bahan organik setelah tanam
Aplikasi selanjutnya dilakukan saat tunas sudah mulai
muncul (1-2 minggu setelah tanam). Pemberian bahan
organik sebagai sumber ZPT alami disesuaikan dengan
perlakuannya masing-masing. Aplikasi dilakukan dengan
cara penyemprotan di seluruh permukaan tajuk bibit
dengan menggunakan hand sprayer, dilakukan secara rutin
setiap 2 minggu sekali. Penyemprotan bahan organik
sebagai sumber ZPT alami pada bibit dilakukan secara
adil hingga seluruh permukaan tajuk terbasahi.
9. Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)
Pengendalian gulma dilakukan secara manual, yaitu
dengan mencabut gulma yang berada dalam polibag.
Pengandalian terhadap hama dan patogen dilakukan dengan
pestisida sesuai prosedur yang berlaku dan terutama
harus disesuaikan dengan jenis jasad pengganggu.
10. Panen
Panen dilakukan setelah tebu berumur 120 hari setelah
tanam (hst). Pemanenan dilakukan secara hati-hati
sampai semua organ dapat dipanen termasuk semua akar.
E. Pengamatan
Pengamatan dilakukan terhadap lingkungan tempat
penelitian dan pertumbuhan bibit tebu. Pengamatan
pertumbuhan tebu dilakukan pada tanaman sampel dan
28
tanaman korban. Tanaman sampel terdiri dari 5 tanaman
pada setiap kombinasi perlakuan. Pengamatan tanaman
sampel dilakukan secara rutin setiap seminggu sekali.
Pengamatan rutin dilakukan untuk mengetahui respon
tanaman terhadap pemberian bahan organik yang berbeda
sebagai sumber ZPT alami. Pengamatan tanaman korban
dilakukan pada umur 40, 80, dan 120 hst atau saat panen.
a. Pengamatan lingkungan
Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap
pertumbuhan tanaman. Pengamatan lingkungan bertujuan
untuk mengetahui pengaruh faktor lingkungan terhadap
perlakuan aplikasi bahan organik sebagai sumber ZPT
alami. Variabel pengamatan lingkungan meliputi:
a. Suhu udara
Suhu udara diukur menggunakan thermometer. Satuan yang
digunakan adalah ºC (derajat celcius). Pengamatan
dilakukan seminggu sekali sekitar pukul 08.00, 12.00,
dan 16.00 WIB sampai pada minggu ke-17.
b. Kelembaban
Kelembaban udara diukur menggunakan hygrometer dalam
satuan %. Pengamatan dilakukan seminggu sekali
sekitar pukul 08.00, 12.00, dan 16.00 WIB sampai pada
minggu ke-17.
c. Intensitas cahaya
Pengukuran intensitas cahaya menggunakan luxmeter.
Pengamatan dilakukan seminggu sekali sekitar pukul
08.00, 12.00, dan 16.00 WIB sampai pada minggu ke-17.
29
d. Curah hujan
Data curah hujan selama berlangsungnya penelitian
dapat diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi
dan Geofisika (BMKG) setempat setelah akhir masa
tanam.
b. Variabel pengamatan tanaman sampel
a. Waktu muncul tunas
Waktu muncul tunas diketahui dengan mengamati waktu
munculnya tunas ke atas permukaan tanah pada awal
masa tanam.
b. Tinggi tunas
Tinggi tunas diukur menggunakan meteran atau
penggaris. Tinggi tunas diukur dari permukaan tanah
hingga ujung daun tertinggi.
c. Jumlah daun pada tunas
Jumlah daun diamati dengan menghitung daun yang
telah membuka sempurna.
d. Diameter tunas
Pengukuran diameter tunas menggunakan jangka sorong
pada nodia terbawah, nodia tengah dan nodia teratas
kemudian dibuat reratanya.
e. Jumlah ruas (internodia) pada tunas
Jumlah ruas pada tunas diketahui dengan menghitung
seluruh ruas yang terdapat pada tunas dari dasar
hingga ujung.
30
f. Panjang ruas (internodia) pada tunas
Panjang internodia pada tunas diukur dari tiga
internodia yang letaknya di atas, tengah, dan bawah,
kemudian dibuat reratanya.
c. Variabel pengamatan tanaman korban
a. Luas daun
Pengukuran luas daun dilakukan dengan menggunakan
metode Gravimetri. Metode ini dilakukan dengan cara
membuat pola daun pada selembar kertas yang seragam.
Luas daun diperoleh dari perbandingan antara berat
pola daun dan berat kertas yang telah diketahui
luasnya.
Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:
Ld=LkBkxBd
Keterangan: Ld = Luas pola daun (cm2)
Lk = Luas kertas pembanding (cm2)
Bd = Berat pola daun (g)
Bk = Berat kertas pembanding (g)
b. Panjang akar utama
Panjang akar utama diukur dari pangkal batang sampai
ujung akar utama dengan menggunakan penggaris atau
meteran.
c. Volume akar
31
Volume akar diketahui dengan memasukkan semua akar
ke dalam gelas piala yang telah diisi air dan
dilihat pertambahan volume yang terjadi. Selisih
antara volume air awal dan volume air akhir
merupakan nilai dari volume akar yang dinyatakan
dalam ml.
d. Bobot segar total
Berat segar total diperoleh dengan menimbang seluruh
bagian tanaman. Berat segar total dinyatakan dalam
gram.
e. Bobot segar tajuk
Berat segar tajuk diperoleh dengan membagi tanaman
menjadi dua bagian tajuk dan akar. Bagian tajuk
kemudian ditimbang dan dinyatakan dalam gram.
f. Bobot segar akar
Berat segar akar diukur menggunakan timbangan dengan
ketelitian dua angka di belakang koma.
g. Bobot kering total
Seluruh bagian tanaman di oven dengan suhu 90-105 ºC
selama 48 jam kemudian dilakukan penimbangan yang
pertama. Setelah itu tanaman dimasukkan lagi ke oven
dan ditimbang setiap 3 jam sekali sampai bobot
kering konstan. Bobot kering konstan diketahui
apabila bobot hasil pengukuran sudah sama dengan
bobot pengukuran sebelumnya.
h. Bobot kering tajuk
32
Bobot kering tajuk dilakukan dengan menimbang tajuk
yang bobot keringnya telah konstan.
i. Bobot kering akar
Bobot kering akar diukur dengan cara yang sama
dengan bobot kering total akan tetapi hanya bagian
akar saja yang ditimbang.
j. Nisbah akar tajuk
Nisbah akar tajuk adalah perbandingan antara bobot
kering akar dan bobot kering tajuk.
d. Analisis Pertumbuhan
Analisis pertumbuhan dilakukan terhadap variabel
sebagai berikut:
a. Laju Asimilasi Bersih (LAB)
Laju asimilasi bersih merupakan kemampuan tanaman
menghasilkan bahan kering hasil asimilasi tiap
satuan luas daun tiap satuan waktu. Rumus
perhitungan adalah sebagai berikut:
LAB=W2−W1T2−T1
xln La2−ln La1La2−La1 g/cm2/minggu
b. Laju Pertumbuhan Nisbi (LPN)
Laju pertumbuhan nisbi merupakan kemampuan tanaman
menghasilkan bahan kering hasil asimilasi tiap
satuan bobot kering awal tiap satuan waktu.
Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:
LPN=ln W2−lnW1T2−T1 g/g/minggu
33
Keterangan:
La = Luas daun (cm2)
La1 = Luas daun awal (cm2)
La2 = Luas daun akhir (cm2)
W1 = Bobot kering awal (g)
W2 = Bobot kering akhir (g)
T1 = Waktu awal (minggu)
T2 = Waktu akhir (minggu)
F. Analisis Data
Data yang akan diperoleh dari hasil pengamatan
dianalisis dengan menggunakan analisis varian (Anova)
taraf 5 %. Apabila terdapat beda nyata antar perlakuan,
dilanjutkan dengan uji Dunnet dengan taraf 5 %. Penentuan
konsentrasi yang optimal untuk masing-masing zat pengatur
tumbuh bersumber bahan organik dilakukan dengan
menggunakan analisis regresi, sedangkan hubungan antar
variabel pengamatan ditentukan dengan analisis korelasi.
34
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Lingkungan
Penelitian ini dilakukan di Banguntapan selama musim
penghujan, yaitu pada bulan Desember 2012 sampai April
2013. Berdasarkan data yang diperoleh dari BMKG (2013),
curah hujan yang terjadi di daerah penelitian mencapai
409 mm pada bulan Desember, 366 mm pada bulan Januari,
268 mm pada bulan Februari, 160 mm pada bulan Maret, dan
155 mm pada bulan April. Kondisi curah hujan yang tinggi
selama penelitian mampu mendukung terjadinya pertunasan
dan pertumbuhan vegetatif tebu yang meliputi tinggi dan
besar batang. Menurut Kuntohartono (1982), curah hujan
yang ideal bagi pertumbuhan awal tebu adalah sekitar 200
mm selama 5-6 bulan. Menurut Soepardiman (1996), apabila
musim kering tiba sebelum pertumbuhan vegetatif berakhir,
maka tanaman tebu yang tidak diairi akan mati sebelum
mencapai tingkat masak.
Faktor lingkungan lain yang diamati selama penelitian
yaitu suhu, kelembaban udara, kecepatan angin, dan
intensitas cahaya. Hasil rata-rata suhu yang dicapai
sekitar 33,5 C, kelembaban udara sekitar 87,62 %,
kecepatan angin sekitar 12,37 km/jam, dan
intensitas cahaya sekitar 625,6 lux. Hal ini masih sesuai
dengan syarat tumbuh tebu, terutama pada fase vegetatif.
Kuntohartono (1982) menyatakan bahwa suhu udara minimum
35
yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman tebu adalah 24
°C, suhu maksimum adalah 34 °C, dan suhu optimum adalah
30 °C. Apabila suhu dibawah 15 °C, pertumbuhan tanaman
akan terhenti. Angin dengan kecepatan kurang lebih 10
km/jam di siang hari berdampak positif bagi pertumbuhan
tebu. Suhu udara, intensitas cahaya, dan kelembaban yang
tinggi dapat meningkatkan laju fotosintesis (Salisbury
and Ross, 1995).
Penelitian ini menggunakan media pasir pantai. Media
ini memiliki porositas yang besar dan laju evaporasi yang
tinggi. Suhu udara, intensitas cahaya, dan kecepatan
angin yang tinggi di tempat penelitian berpotensi
meningkatkan kehilangan lengas dalam tanah, terutama pada
jenis tanah pasir. Hal ini dapat menyebabkan cekaman
kekeringan pada tanaman. Tingginya curah hujan dan
dilakukannya kegiatan penyiraman selama penelitian dapat
mengurangi kondisi tersebut sehingga tebu masih dapat
tumbuh dengan baik. Penggunaan bahan organik berupa
kompos yang dicampurkan ke dalam media tanam juga dapat
meningkatkan daya simpan air bagi tanaman.
B. Pengaruh Macam dan Konsentrasi Bahan Organik sebagaiSumber Zat Pengatur Tumbuh Alami terhadap PertumbuhanBibit Tebu
1. Panjang Akar Utama
Tabel 4.1.Pengaruh macam dan konsentrasi bahan organiksebagai sumber zat pengatur tumbuh alamiterhadap panjang akar utama bibit tebu
36
Perlakuan Panjang Akar Utama (cm)40 hst 80 hst 120 hst
Kontrol 41,02 68,46 184,03
Air kelapa muda 25 % 59,00 ns
75,90 ns
206,21 ns
Air kelapa muda 50 % 55,70 ns
69,40 ns
180,36 ns
Air kelapa muda 75 % 53,50 ns
64,16 ns
171,17 ns
Urin sapi perah 25 % 52,92 ns
77,74 ns
201,15 ns
Urin sapi perah 50 % 36,06 ns
69,01 ns
180,36 ns
Urin sapi perah 75 % 29,89 ns
64,16 ns
168,99 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 25 %
43,20 ns
74,64 ns
198,76 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 50 %
37,20 ns
61,50 ns
164,72 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 75 %
32,26 ns
58,37 ns
155,20 ns
Keterangan: ns = tidak berbeda nyata dengan kontrol, * =berbeda nyata dengan kontrol
Berdasarkan analisis varian, terdapat perbedaan
nyata pada perlakuan macam dan konsentrasi bahan
organik sebagai sumber zat pengatur tumbuh alami
terhadap panjang akar utama bibit tebu pada umur 40
hst, namun uji lanjut Dunnet memberikan hasil yang
tidak berbeda nyata untuk semua perlakuan jika
dibandingkan dengan kontrol. Pada umur tebu 80 dan 120
hst, tidak terdapat beda nyata berdasarkan analisis
varian. Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa perlakuan macam
dan konsentrasi bahan organik sebagai sumber zat
pengatur tumbuh alami tidak berpengaruh nyata terhadap
variabel panjang akar utama bibit tebu baik pada umur
37
40, 80, ataupun 120 hst bila dibandingkan dengan
kontrol. Perlakuan air kelapa muda 25 %, air kelapa
muda 50 %, air kelapa muda 75 %, urin sapi perah 25 %,
urin sapi perah 50 %, urin sapi perah 75 %, ekstrak
kecambah kacang hijau 25 %, ekstrak kecambah kacang
hijau 50 %, dan ekstrak kecambah kacang hijau 75 %
secara signifikan tidak mampu meningkatkan panjang
akar utama bibit tebu apabila dibandingkan dengan
perlakuan tanpa bahan organik. Panjang akar bibit tebu
pada umur 40 hst rata-rata berkisar 29-59 cm.
Panjang akar bibit tebu pada umur 80 hst rata-rata
berkisar 58-77 cm, sedangkan panjang ruas bibit tebu
pada umur 120 hst rata-rata berkisar 155-206
cm.
Hasil yang tidak berbeda nyata pada variabel
panjang akar utama diduga dapat terjadi karena
perakaran yang terdapat pada tebu merupakan perakaran
serabut. Pada perakaran serabut, akar primer tidak
dapat bertahan lama dalam pertumbuhan tanaman dan
segera mengering, lalu dari pangkal akar tersebut akan
muncul akar baru yang disebut akar adventif. Akar-akar
adventif ini yang mempengaruhi besar kecilnya volume
akar.
2. Volume Akar
Tabel 4.2.Pengaruh macam dan konsentrasi bahan organiksebagai sumber zat pengatur tumbuh alamiterhadap volume akar bibit tebu
38
Perlakuan Volume Akar (ml)40 hst 80 hst 120 hst
Kontrol 8,00 135,30 379,50
Air kelapa muda 25 % 38,00 *
302,00 *
3678,80 *
Air kelapa muda 50 % 30,40 *
230,00 ns
2485,20 *
Air kelapa muda 75 % 24,30 ns
194,00 ns
1507,00 ns
Urin sapi perah 25 % 25,30 ns
278,00 *
1173,80 ns
Urin sapi perah 50 % 11,50 ns
223,78 ns
609,00ns
Urin sapi perah 75 % 9,66ns
136,00 ns
341,90ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 25 %
11,20 ns
218,89 ns
533,50ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 50 %
7,50ns
128,00 ns
488,10ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 75 %
5,90ns
110,00 ns
253,30ns
Keterangan: ns = tidak berbeda nyata dengan kontrol, * =berbeda nyata dengan kontrol
Perlakuan macam dan konsentrasi bahan organik
sebagai sumber zat pengatur tumbuh alami berpengaruh
nyata terhadap variabel volume akar berdasarkan
analisis varian. Berdasarkan uji lanjut Dunnet (Tabel
4.2), hasilnya berbeda nyata baik pada umur tebu 40,
80, ataupun 120 hst. Pada umur tebu 40 dan 120
hst, pemberian air kelapa muda 25 dan 50 % mampu
menghasilkan volume akar yang lebih besar dibandingkan
dengan kontrol (tanpa bahan organik). Peningkatan
konsentrasi air kelapa muda hingga 75 % justru
menghasilkan volume akar yang lebih kecil dan tidak
berbeda nyata dengan kontrol (tanpa bahan organik),
39
sedangkan untuk perlakuan urin sapi perah 50 %, urin
sapi perah 75 %, ekstrak kecambah kacang hijau 25 %,
ekstrak kecambah kacang hijau 50 %, dan ekstrak
kecambah kacang hijau 75 %, nilai volume akar bibit
tebu yang dihasilkan tidak berbeda nyata jika
dibandingkan dengan kontrol (tanpa bahan organik)
walaupun terlihat adanya kecenderungan penurunan nilai
volume akar seiring dengan penambahan konsentrasi pada
masing-masing bahan organik.
Pada umur tebu 80 hst, pemberian air kelapa muda
25 % secara nyata mampu menghasilkan volume akar bibit
tebu yang lebih besar dibandingkan kontrol (tanpa
bahan organik). Penambahan konsentrasi air kelapa muda
hingga 50-75 % justru menurunkan nilai volume akar
bibit tebu dan tidak berbeda nyata dengan kontrol
(tanpa bahan organik). Sama halnya dengan perlakuan
urin sapi perah dan ekstrak kecambah kacang hijau baik
pada konsentrasi 25, 50, ataupun 75 %, volume akar
yang dihasilkan tidak berbeda nyata dengan kontrol
(tanpa bahan organik) walaupun terlihat adanya
kecenderungan penurunan nilai volume akar seiring
dengan penambahan konsentrasi pada masing-masing bahan
organik.
3. Jumlah Daun
Tabel 4.3.Pengaruh macam dan konsentrasi bahan organiksebagai sumber zat pengatur tumbuh alamiterhadap jumlah daun bibit tebu
40
Perlakuan Jumlah Daun6 mst 12 mst 17 mst
Kontrol 8,00 13,40 19,20Air kelapa muda 25 % 9,40 * 14,80 ns 21,40 nsAir kelapa muda 50 % 8,40 ns 14,40 ns 20,80 nsAir kelapa muda 75 % 8,40 ns 14,00 ns 20,20 nsUrin sapi perah 25 % 8,40 ns 13,80 ns 20,00 nsUrin sapi perah 50 % 8,20 ns 13,60 ns 19,60 nsUrin sapi perah 75 % 7,60 ns 13,00 ns 18,80 nsEkstrak kecambah kacang hijau 25 % 7,80 ns 13,60 ns 19,60 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 50 % 7,40 ns 13,20 ns 19,00 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 75 % 7,20 ns 12,60 ns 18,20 nsKeterangan: ns = tidak berbeda nyata dengan kontrol, * =
berbeda nyata dengan kontrol
Pemberian bahan organik sebagai sumber zat
pengatur tumbuh alami berpengaruh nyata terhadap
variabel jumlah daun berdasarkan analisis varian baik
pada umur tebu 6, 12, maupun 17 mst. Berdasarkan uji
lanjut Dunnet (Tabel 4.3), perbedaan nyata hanya
nampak pada umur tebu 6 mst. Pada umur tebu 6 mst,
pemberian air kelapa muda 25 % secara nyata mampu
menghasilkan bibit tebu dengan jumlah daun lebih
banyak dibandingkan kontrol (tanpa bahan organik).
Penambahan konsentrasi air kelapa muda hingga 50-75 %
justru menurunkan nilai jumlah daun bibit tebu dan
tidak berbeda nyata dengan kontrol (tanpa bahan
organik). Sama halnya dengan perlakuan urin sapi perah
dan ekstrak kecambah kacang hijau baik pada
konsentrasi 25, 50, ataupun 75 %, jumlah daun bibit
tebu yang dihasilkan tidak berbeda nyata dengan
41
kontrol (tanpa bahan organik) walaupun terlihat adanya
kecenderungan penurunan nilai jumlah daun seiring
dengan penambahan konsentrasi pada masing-masing bahan
organik.
Pada umur 12 dan 17 mst, tidak nampak adanya beda
nyata berdasarkan uji lanjut Dunnet. Pada umur
tersebut, pemberian air kelapa muda 25 %, air kelapa
muda 50 %, air kelapa muda 75 %, urin sapi perah 25 %,
urin sapi perah 50 %, urin sapi perah 75 %, ekstrak
kecambah kacang hijau 25 %, ekstrak kecambah kacang
hijau 50 %, dan ekstrak kecambah kacang hijau 75 %
diketahui tidak berpengaruh nyata terhadap variabel
jumlah daun jika dibandingkan dengan kontrol (tanpa
bahan organik).
4. Luas Daun
Pada tanaman tingkat tinggi, daun berfungsi
sebagai organ utama fotosintesis. Jaringan
fotosintesis yang hijau pada daun ini secara efisien
dapat menyerap radiasi matahari yang dibutuhkan oleh
tanaman. Tanaman cenderung menginvestasikan sebagian
besar awal pertumbuhan dalam bentuk penambahan luas
daun (Gardner et al., 1991).
Tabel 4.4 menunjukkan adanya pengaruh yang nyata
pada perlakuan macam dan konsentrasi bahan organik
sebagai sumber zat pengatur tumbuh alami terhadap luas
daun bibit tebu baik pada umur 40, 80, maupun 120 hst
42
apabila dibandingkan dengan kontrol. Pemberian
perlakuan air kelapa muda 25 dan 50 % secara nyata
mampu menghasilkan daun yang lebih luas dibandingkan
dengan perlakuan tanpa bahan organik pada umur tebu
40, 80, dan 120 hst. Peningkatan konsentrasi air
kelapa muda hingga 75 % justru menghasilkan daun yang
lebih sempit dan tidak berbeda nyata dengan kontrol
(tanpa bahan organik). Meskipun terlihat adanya
kecenderungan penurunan nilai luas daun seiring dengan
penambahan konsentrasi pada masing-masing bahan
organik, baik perlakuan urin sapi perah 25 %, urin
sapi perah 50 %, urin sapi perah 75 %, ekstrak
kecambah kacang hijau 25 %, ekstrak kecambah kacang
hijau 50 %, ataupun ekstrak kecambah kacang hijau 75
%, nilai luas daun bibit tebu yang dihasilkan tidak
berbeda nyata jika dibandingkan dengan perlakuan tanpa
bahan organik.
Tabel 4.4.Pengaruh macam dan konsentrasi bahan organiksebagai sumber zat pengatur tumbuh alamiterhadap luas daun bibit tebu
Perlakuan Luas Daun (cm2)40 hst 80 hst 120 hst
Kontrol 349,30 1572,70 4246,40
Air kelapa muda 25 % 961,10 *
2420,90*
6519,90*
Air kelapa muda 50 % 744,50 *
2407,10*
6459,60*
Air kelapa muda 75 % 726,50 ns
1960,60ns
5564,60ns
Urin sapi perah 25 % 719,70 ns
2113,60ns
5677,50ns
Urin sapi perah 50 % 558,00 ns
1830,90ns
5265,00ns
43
Urin sapi perah 75 % 436,60 ns
1667,30ns
4942,30ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 25 %
421,70 ns
2059,30ns
4679,60ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 50 %
411,20 ns
1744,80ns
4504,30ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 75 %
280,80 ns
1306,20ns
3527,70ns
Keterangan: ns = tidak berbeda nyata dengan kontrol, * =berbeda nyata dengan kontrol
5. Laju Asimilasi Bersih (LAB)
Laju asimilasi bersih merupakan laju pertambahan
bobot kering total tanaman per satuan luas daun per
satuan waktu selama periode tertentu. Berdasarkan
analisis varian, tidak terdapat pengaruh yang
signifikan pada perlakuan macam dan konsentrasi bahan
organik sebagai sumber zat pengatur tumbuh alami
terhadap laju asimilasi bersih bibit tebu pada umur
40-80 dan 80-120 hst. Pada umur-umur tersebut,
perlakuan air kelapa muda 25 %, air kelapa muda 50 %,
air kelapa muda 75 %, urin sapi perah 25 %, urin sapi
perah 50 %, urin sapi perah 75 %, ekstrak kecambah
kacang hijau 25 %, ekstrak kecambah kacang hijau 50 %,
dan ekstrak kecambah kacang hijau 75 % tidak
berpengaruh secara nyata terhadap laju asimilasi
bersih bibit tebu.
Tabel 4.5.Pengaruh macam dan konsentrasi bahan organiksebagai sumber zat pengatur tumbuh alamiterhadap LAB bibit tebuPerlakuan LAB (g/cm2/minggu)
44
40-80 hst 80-120 hstKontrol 0,019 0,017Air kelapa muda 25 % 0,025 ns 0,031 nsAir kelapa muda 50 % 0,019 ns 0,020 nsAir kelapa muda 75 % 0,017 ns 0,018 nsUrin sapi perah 25 % 0,024 ns 0,028 nsUrin sapi perah 50 % 0,018 ns 0,017 nsUrin sapi perah 75 % 0,017 ns 0,015 nsEkstrak kecambah kacang hijau 25 % 0,027 ns 0,026 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 50 % 0,025 ns 0,024 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 75 % 0,015 ns 0,013 nsKeterangan: ns = tidak berbeda nyata dengan kontrol, * =
berbeda nyata dengan kontrol
Nilai LAB nampak mengalami perubahan seiring
dengan pertambahan umur tanaman. Perubahan nilai LAB
ini diduga berkaitan dengan peningkatan luas daun.
Apabila penyerapan radiasi matahari menjadi tidak
efisien akibat adanya peningkatan luas daun dan
rapatnya jarak antar tanaman yang dapat menyebabkan
daun menjadi saling naung, maka LAB akan menurun
seiring dengan menurunnya kemampuan berfotosintesis.
Namun apabila peningkatan luas daun sebanding dengan
keefisienannya dalam menyerap radiasi matahari, maka
nilai LAB justru akan semakin meningkat seiring dengan
meningkatnya kemampuan berfotosintesis. Seperti yang
diungkapkan oleh Hunt (1978), LAB itu tidak konstan
terhadap waktu, tetapi menunjukkan suatu kecenderungan
penurunan ontogenetik seiring dengan usia tanaman.
Kecenderungan ini dipercepat oleh adanya lingkungan
yang tidak menguntungkan. Perolehan bobot kering per45
satuan permukaan daun menurun dengan bertambahnya daun
baru, karena adanya saling menaungi.
6. Laju Pertumbuhan Nisbi (LPN)
Laju pertumbuhan nisbi merupakan peningkatan bobot
kering total dalam satuan interval waktu dalam
hubungannya dengan berat awal (Gardner et al., 1991).
Analisis varian menunjukkan hasil yang tidak berbeda
nyata pada perlakuan macam dan konsentrasi bahan
organik sebagai sumber zat pengatur tumbuh alami
terhadap variabel laju pertumbuhan nisbi bibit tebu
pada umur 40-80 hst, sedangkan hasil yang berbeda
nyata ditunjukkan pada bibit tebu berumur 80-120 hst.
Berdasarkan uji lanjut Dunnet pada umur tebu 80-120
hst, didapatkan pula hasil yang tidak berbeda nyata
pada seluruh perlakuan yang dibandingkan dengan
kontrol.
Tabel 4.6.Pengaruh macam dan konsentrasi bahan organiksebagai sumber zat pengatur tumbuh alamiterhadap LPN bibit tebu
Perlakuan LPN (g/g/minggu)40-80 hst 80-120 hst
Kontrol 0,584 0,240Air kelapa muda 25 % 0,513 ns 0,242 nsAir kelapa muda 50 % 0,508 ns 0,245 nsAir kelapa muda 75 % 0,471 ns 0,241 nsUrin sapi perah 25 % 0,554 ns 0,242 ns
46
Urin sapi perah 50 % 0,555 ns 0,225 nsUrin sapi perah 75 % 0,585 ns 0,232 nsEkstrak kecambah kacang hijau 25 % 0,658 ns 0,242 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 50 % 0,658 ns 0,244 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 75 % 0,544 ns 0,234 nsKeterangan: ns = tidak berbeda nyata dengan kontrol, * =
berbeda nyata dengan kontrol
Pada umur 40, 80, dan 120 hst, terlihat bahwa
perlakuan air kelapa muda 25 %, air kelapa muda 50 %,
air kelapa muda 75 %, urin sapi perah 25 %, urin sapi
perah 50 %, urin sapi perah 75 %, ekstrak kecambah
kacang hijau 25 %, ekstrak kecambah kacang hijau 50 %,
dan ekstrak kecambah kacang hijau 75 % tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap laju
pertumbuhan nisbi bibit tebu apabila dibandingkan
dengan perlakuan tanpa bahan organik (Tabel 4.6).
Rerata LPN bibit tebu pada umur 40-80 hst adalah
sekitar 0,47-0,66 g/g/minggu, sedangkan rerata LPN
bibit tebu pada saat umur 80-120 hst adalah sekitar
0,22-0,24 g/g/minggu.
7. Waktu Muncul Tunas
Tabel 4.7.Pengaruh macam dan konsentrasi bahan organiksebagai sumber zat pengatur tumbuh alamiterhadap waktu mucul tunas tebu
Perlakuan Waktu Muncul Tunas (hst)Kontrol 7,40Air kelapa muda 25 % 4,60 nsAir kelapa muda 50 % 4,80 nsAir kelapa muda 75 % 5,60 ns
47
Urin sapi perah 25 % 6,60 nsUrin sapi perah 50 % 7,00 nsUrin sapi perah 75 % 7,40 nsEkstrak kecambah kacang hijau 25 % 7,00 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 50 % 7,60 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 75 % 8,40 nsKeterangan: ns = tidak berbeda nyata dengan kontrol, * =
berbeda nyata dengan kontrol
Waktu muncul tunas diketahui dengan cara mengamati
waktu kemunculan tunas tebu ke atas permukaan tanah
dalam hitungan hari setelah tanam. Hasil analisis
varian menunjukkan bahwa perlakuan macam dan
konsentrasi bahan organik sebagai sumber zat pengatur
tumbuh alami berpengaruh nyata terhadap waktu muncul
tunas, tetapi uji lanjut Dunnet menunjukkan hasil yang
tidak berbeda nyata. Hal ini dikarenakan pada analisis
varian hasil rerata masing-masing perlakuan
dibandingkan satu sama lain, sedangkan pada uji lanjut
Dunnet hasil rerata perlakuan macam dan konsentrasi
bahan organik hanya dibandingkan dengan kontrol.
Seperti yang terdapat pada Tabel 4.7, aplikasi ketiga
macam bahan organik (air kelapa muda, urin sapi perah,
dan ekstrak kecambah kacang hijau) baik pada
konsentrasi 25, 50, ataupun 75 % menghasilkan waktu
muncul tunas yang tidak berbeda dengan perlakuan
kontrol (tanpa bahan organik). Perendaman bahan tanam
dalam bahan organik sebagai sumber zat pengatur tumbuh
alami tersebut selama 2 jam sebelum penanaman tidak
48
berpengaruh secara nyata terhadap waktu muncul tunas
tebu. Waktu muncul tunas rata-rata berkisar 4-8 hst.
8. Bobot Segar Akar
Tabel 4.8.Pengaruh macam dan konsentrasi bahan organiksebagai sumber zat pengatur tumbuh alamiterhadap bobot segar akar bibit tebu
Perlakuan Bobot Segar Akar (g)40 hst 80 hst 120 hst
Kontrol 5,66 119,82 318,44
Air kelapa muda 25 % 32,25 * 298,58 * 793,54
*
Air kelapa muda 50 % 24,90 * 219,14 * 582,42
*
Air kelapa muda 75 % 18,98 ns
179,14 ns
476,10 ns
Urin sapi perah 25 % 18,19 ns
211,44 ns
566,50 ns
Urin sapi perah 50 % 11,11 ns
182,10 ns
483,97 ns
Urin sapi perah 75 % 6,99ns
135,76 ns
416,24 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 25 %
9,98ns
181,88 ns
483,38 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 50 %
5,97ns
156,62 ns
360,82 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 75 %
4,45ns
114,27 ns
303,69 ns
Keterangan: ns = tidak berbeda nyata dengan kontrol, * =berbeda nyata dengan kontrol
Berdasarkan analisis varian, pemberian bahan
organik sebagai sumber zat pengatur tumbuh alami
berpengaruh nyata terhadap variabel bobot segar akar.49
Berdasarkan uji lanjut Dunnet (Tabel 4.8), perbedaan
nyata ditunjukkan baik pada umur tebu 40, 80, maupun
120 hst. Pada umur-umur tersebut, pemberian air kelapa
muda 25 % dan 50 % secara nyata mampu menghasilkan
nilai bobot segar akar bibit tebu yang lebih tinggi
dibandingkan kontrol (tanpa bahan organik). Penambahan
konsentrasi air kelapa muda hingga 75 % justru
menurunkan nilai bobot segar akar bibit tebu dan tidak
berbeda nyata dengan kontrol (tanpa bahan organik).
Sama halnya dengan perlakuan urin sapi perah 25 %,
urin sapi perah 50 %, urin sapi perah 75 %, ekstrak
kecambah kacang hijau 25 %, ekstrak kecambah kacang
hijau 50 %, dan ekstrak kecambah kacang hijau 75 %,
hasilnya tidak berbeda nyata dengan kontrol (tanpa
bahan organik) walaupun terlihat adanya kecenderungan
penurunan nilai bobot segar akar seiring dengan
penambahan konsentrasi pada masing-masing bahan
organik.
9. Bobot Segar Tajuk
Tabel 4.9.Pengaruh macam dan konsentrasi bahan organiksebagai sumber zat pengatur tumbuh alamiterhadap bobot segar tajuk bibit tebuPerlakuan Bobot Segar Tajuk (g)
50
40 hst 80 hst 120 hst
Kontrol 21,62 157,63 625,00
Air kelapa muda 25 % 66,43 * 317,48 * 1256,20
*
Air kelapa muda 50 % 45,27 ns 308,06 * 1221,10
*
Air kelapa muda 75 % 43,58 ns
206,41 ns
816,70 ns
Urin sapi perah 25 % 44,60 ns
264,12 ns
1046,30ns
Urin sapi perah 50 % 29,03 ns
221,28 ns
798,80 ns
Urin sapi perah 75 % 28,43 ns
201,50 ns
877,70 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 25 %
26,95 ns
250,55 ns
997,60 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 50 %
24,36 ns
180,51 ns
716,20 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 75 %
15,64 ns
124,09 ns
492,10 ns
Keterangan: ns = tidak berbeda nyata dengan kontrol, * =berbeda nyata dengan kontrol
Pemberian bahan organik sebagai sumber zat
pengatur tumbuh alami berpengaruh nyata terhadap
variabel bobot segar tajuk bibit tebu berdasarkan
analisis varian. Uji lanjut Dunnet (Tabel 4.9) juga
memberikan hasil yang berbeda nyata baik pada umur
tebu 40, 80, maupun 120 hst. Pada umur tebu 40
hst, perlakuan air kelapa muda 25 % mampu menghasilkan
nilai bobot segar tajuk yang lebih tinggi dibandingkan
51
dengan kontrol (tanpa bahan organik). Peningkatan
konsentrasi air kelapa muda hingga 50-75 % justru
menghasilkan nilai bobot segar tajuk yang lebih rendah
dan tidak berbeda nyata dengan kontrol (tanpa bahan
organik). Begitu juga dengan perlakuan lainnya, yaitu
perlakuan urin sapi perah dan ekstrak kecambah kacang
hijau baik pada konsentrasi 25, 50, ataupun 75 %,
hasilnya tidak berbeda nyata dengan kontrol (tanpa
bahan organik). Jadi, dapat dikatakan bahwa perlakuan
air kelapa muda 50 %, air kelapa muda 75 %, urin sapi
perah 25 %, urin sapi perah 50 %, urin sapi perah 75
%, ekstrak kecambah kacang hijau 25 %, ekstrak
kecambah kacang hijau 50 %, dan ekstrak kecambah
kacang hijau 75 % pada umur 40 hst secara signifikan
tidak mampu meningkatkan nilai bobot segar tajuk bibit
tebu bila dibandingkan dengan kontrol (tanpa bahan
organik) meskipun terlihat adanya kecenderungan
penurunan nilai bobot segar tajuk seiring dengan
penambahan konsentrasi pada masing-masing bahan
organik.
Pada umur tebu 80 dan 120 hst, pemberian air
kelapa muda 25 % dan 50 % secara nyata mampu
menghasilkan nilai bobot segar tajuk yang lebih tinggi
dibandingkan kontrol (tanpa bahan organik). Penambahan
konsentrasi air kelapa muda hingga 75 % justru
menurunkan nilai bobot segar tajuk bibit tebu dan
tidak berbeda nyata dengan kontrol (tanpa bahan
52
organik). Sama halnya dengan perlakuan urin sapi perah
dan ekstrak kecambah kacang hijau baik pada
konsentrasi 25, 50, ataupun 75 %, bobot segar tajuk
yang dihasilkan tidak berbeda nyata dengan kontrol
(tanpa bahan organik).
10.Bobot Segar Total
Tabel 4.10. Pengaruh macam dan konsentrasi bahanorganik sebagai sumber zat pengatur tumbuhalami terhadap bobot segar total bibit tebu
Perlakuan Bobot Segar Total (g)40 hst 80 hst 120 hst
Kontrol 27,28 277,44 943,50
Air kelapa muda 25 % 98,68 *
616,05 *
2049,80 *
Air kelapa muda 50 % 70,16 ns
527,20 *
1803,50 *
Air kelapa muda 75 % 62,55 ns
385,55 ns
1292,80 ns
Urin sapi perah 25 % 62,79 ns
475,56 *
1612,80 ns
Urin sapi perah 50 % 40,13 ns
403,38 ns
1282,70 ns
Urin sapi perah 75 % 35,41 ns
337,26 ns
1294,00 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 25 %
36,93 ns
432,42 ns
1480,90 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 50 %
30,33 ns
337,12 ns
1077,00 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 75 %
20,08 ns
238,36 ns
795,80ns
Keterangan: ns = tidak berbeda nyata dengan kontrol, * =berbeda nyata dengan kontrol
Bobot segar total merupakan penjumlahan dari bobot
segar akar dan bobot segar tajuk. Hasil analisis
varian menunjukkan bahwa perlakuan macam dan53
konsentrasi bahan organik sebagai sumber zat pengatur
tumbuh alami berpengaruh nyata terhadap variabel bobot
segar total. Berdasarkan uji lanjut Dunnet (Tabel
4.10), hasilnya juga berbeda nyata baik pada umur tebu
40, 80, ataupun 120 hst. Pada umur tebu 40 hst,
pemberian air kelapa muda 25 % mampu menghasilkan
nilai bobot segar total yang lebih tinggi dibandingkan
dengan kontrol (tanpa bahan organik). Peningkatan
konsentrasi air kelapa muda hingga 50-75 % justru
menghasilkan nilai bobot segar total yang lebih rendah
dan tidak berbeda nyata dengan kontrol (tanpa bahan
organik), sedangkan untuk perlakuan urin sapi perah 25
%, urin sapi perah 50 %, urin sapi perah 75 %, ekstrak
kecambah kacang hijau 25 %, ekstrak kecambah kacang
hijau 50 %, dan ekstrak kecambah kacang hijau 75 %,
nilai bobot segar total bibit tebu yang dihasilkan
tidak berbeda nyata jika dibandingkan dengan kontrol
(tanpa bahan organik) walaupun nampak adanya
kecenderungan penurunan nilai bobot segar total
seiring dengan penambahan konsentrasi pada masing-
masing bahan organik.
Pada umur tebu 80 hst, nilai bobot segar total
yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan
perlakuan tanpa bahan organik terdapat pada perlakuan
air kelapa muda 25 %, air kelapa muda 50 %, dan urin
sapi perah 25 %. Perlakuan air kelapa muda 75 %, urin
sapi perah 50 %, urin sapi perah 75 %, ekstrak
54
kecambah kacang hijau 25 %, ekstrak kecambah kacang
hijau 50 %, dan ekstrak kecambah kacang hijau 75 %
tidak berpengaruh nyata terhadap variabel bobot segar
total jika dibandingkan dengan kontrol. Peningkatan
konsentrasi pada masing-masing bahan organik cenderung
menghasilkan nilai bobot segar total bibit tebu yang
lebih rendah.
Pada umur tebu 120 hst, pemberian air kelapa muda
25 % dan 50 % secara nyata mampu menghasilkan nilai
bobot segar total yang lebih tinggi dibandingkan
kontrol (tanpa bahan organik). Penambahan konsentrasi
air kelapa muda hingga 75 % justru menurunkan nilai
bobot segar total bibit tebu dan tidak berbeda nyata
dengan kontrol (tanpa bahan organik). Sama halnya
dengan perlakuan urin sapi perah dan ekstrak kecambah
kacang hijau baik pada konsentrasi 25, 50, ataupun 75
%, bobot segar total yang dihasilkan tidak berbeda
nyata dengan kontrol walau nampak adanya kecenderungan
penurunan nilai bobot segar total seiring dengan
penambahan konsentrasi pada masing-masing bahan
organik.
11.Bobot Kering Akar
Tabel 4.11 menunjukkan adanya pengaruh yang
signifikan pada perlakuan macam dan konsentrasi bahan
organik sebagai sumber zat pengatur tumbuh alami
terhadap bobot kering akar baik pada umur 40, 80,
55
maupun 120 hst jika dibandingkan dengan kontrol.
Pemberian perlakuan air kelapa muda 25 % secara nyata
mampu menghasilkan nilai bobot kering akar yang lebih
tinggi dibandingkan dengan perlakuan tanpa bahan
organik pada umur tebu 40, 80, dan 120 hst.
Peningkatan konsentrasi air kelapa muda hingga 50-75 %
justru menghasilkan nilai bobot kering akar yang lebih
rendah dan tidak berbeda nyata dengan kontrol (tanpa
bahan organik). Meskipun terlihat adanya kecenderungan
penurunan nilai bobot kering akar seiring dengan
penambahan konsentrasi pada masing-masing bahan
organik, baik perlakuan urin sapi perah 25 %, urin
sapi perah 50 %, urin sapi perah 75 %, ekstrak
kecambah kacang hijau 25 %, ekstrak kecambah kacang
hijau 50 %, ataupun ekstrak kecambah kacang hijau 75
%, nilai bobot kering akar bibit tebu yang dihasilkan
tidak berbeda nyata jika dibandingkan dengan perlakuan
tanpa bahan organik.
Tabel 4.11. Pengaruh macam dan konsentrasi bahanorganik sebagai sumber zat pengatur tumbuhalami terhadap bobot kering akar bibit tebu
Perlakuan Bobot Kering Akar (g)40 hst 80 hst 120 hst
Kontrol 0,64 32,09 180,21
Air kelapa muda 25 % 4,67 * 90,90 * 510,16 *
Air kelapa muda 50 % 2,84 ns
68,11 ns
382,35 ns
Air kelapa muda 75 % 2,68 ns
48,06 ns
269,73 ns
Urin sapi perah 25 % 2,13 ns
75,96 ns
426,48 ns
56
Urin sapi perah 50 % 1,20 ns
33,30 ns
186,98 ns
Urin sapi perah 75 % 0,77 ns
31,19 ns
175,10 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 25 %
0,73 ns
64,46 ns
363,97 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 50 %
0,50 ns
55,63 ns
312,47 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 75 %
0,38 ns
20,82 ns
116,92 ns
Keterangan: ns = tidak berbeda nyata dengan kontrol, * =berbeda nyata dengan kontrol
12.Bobot Kering Tajuk
Adanya pengaruh yang signifikan pada perlakuan
macam dan konsentrasi bahan organik sebagai sumber zat
pengatur tumbuh alami terhadap bobot kering tajuk baik
pada umur 40, 80, maupun 120 hst jika dibandingkan
dengan kontrol ditunjukkan pada Tabel 4.12. Pada umur
tebu 40 hst, pemberian air kelapa muda 25 %, air
kelapa muda 50 %, dan urin sapi perah 25 % secara
nyata mampu menghasilkan nilai bobot kering tajuk yang
lebih tinggi dibandingkan kontrol (tanpa bahan
organik). Penambahan konsentrasi air kelapa muda
hingga 75 % dan urin kelapa muda hingga 50-75 % justru
menurunkan nilai bobot kering tajuk bibit tebu dan
tidak berbeda nyata dengan kontrol (tanpa bahan
organik). Perlakuan urin sapi perah dan ekstrak
kecambah kacang hijau baik pada konsentrasi 25, 50,
ataupun 75 %, bobot kering tajuk yang dihasilkan tidak
berbeda nyata dengan kontrol meski terlihat adanya
57
kecenderungan penurunan nilai bobot kering tajuk
seiring dengan penambahan konsentrasi pada masing-
masing bahan organik.
Tabel 4.12. Pengaruh macam dan konsentrasi bahanorganik sebagai sumber zat pengatur tumbuhalami terhadap bobot kering tajuk bibit tebu
Perlakuan Bobot Kering Tajuk (g)40 hst 80 hst 120 hst
Kontrol 2,40 52,60 149,62
Air kelapa muda 25 % 7,01 *
132,32 *
375,81 *
Air kelapa muda 50 % 5,72 *
85,04ns
241,05 ns
Air kelapa muda 75 % 4,62 ns
72,00ns
204,15 ns
Urin sapi perah 25 % 5,14 *
113,28 ns
322,86 ns
Urin sapi perah 50 % 3,17 ns
77,53ns
219,79 ns
Urin sapi perah 75 % 3,01 ns
60,08ns
171,00 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 25 %
3,05 ns
86,77ns
237,36 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 50 %
2,55 ns
73,66ns
209,53 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 75 %
2,24 ns
38,25ns
108,42 ns
Keterangan: ns = tidak berbeda nyata dengan kontrol, * =berbeda nyata dengan kontrol
Pada umur tebu 80 dan 120 hst, perlakuan air
kelapa muda 25 % mampu menghasilkan nilai bobot kering
tajuk yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol
(tanpa bahan organik). Peningkatan konsentrasi air
kelapa muda hingga 50-75 % justru menghasilkan nilai
bobot kering tajuk yang lebih rendah dan tidak berbeda
nyata dengan kontrol (tanpa bahan organik). Begitu
58
juga dengan perlakuan lainnya, yaitu perlakuan urin
sapi perah dan ekstrak kecambah kacang hijau baik pada
konsentrasi 25, 50, ataupun 75 %, hasilnya tidak
berbeda nyata dengan kontrol (tanpa bahan organik).
Jadi, dapat dikatakan bahwa perlakuan air kelapa muda
50 %, air kelapa muda 75 %, urin sapi perah 25 %, urin
sapi perah 50 %, urin sapi perah 75 %, ekstrak
kecambah kacang hijau 25 %, ekstrak kecambah kacang
hijau 50 %, dan ekstrak kecambah kacang hijau 75 %
pada umur tebu 80 dan 120 hst secara signifikan tidak
mampu meningkatkan nilai bobot kering tajuk bibit tebu
bila dibandingkan dengan kontrol.
13.Bobot Kering Total
Tabel 4.13. Pengaruh macam dan konsentrasi bahanorganik sebagai sumber zat pengatur tumbuhalami terhadap bobot kering total bibit tebu
Perlakuan Bobot Kering Total (g)40 hst 80 hst 120 hst
Kontrol 3,03 84,69 329,80
Air kelapa muda 25 % 11,68 *
223,22 *
886,00 *
Air kelapa muda 50 % 8,56*
153,16 ns
623,40 ns
Air kelapa muda 75 % 7,29*
120,06 ns
473,90 ns
Urin sapi perah 25 % 7,27*
189,24 *
749,30 *
Urin sapi perah 50 % 4,36ns
110,83 ns
406,80 ns
Urin sapi perah 75 % 3,78ns
91,27ns
346,10 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 25 %
3,79ns
151,23 ns
601,30 ns
59
Ekstrak kecambah kacang hijau 50 %
3,05ns
129,29 ns
522,00 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 75 %
2,61ns
59,07ns
225,30 ns
Keterangan: ns = tidak berbeda nyata dengan kontrol, * =berbeda nyata dengan kontrol
Bobot kering total diperoleh dari penjumlahan
bobot kering tajuk dengan bobot kering akar. Bobot
kering total ini merupakan hasil penimbunan hasil
bersih asimilat sepanjang pertumbuhan tanaman. Hasil
bersih asimilat umumnya ditranslokasikan ke seluruh
tubuh tanaman untuk pertumbuhan, perkembangan,
cadangan makanan, dan pengelolaan sel (Gardner et al.,
1991).
Hasil analisis varian menunjukkan bahwa perlakuan
macam dan konsentrasi bahan organik sebagai sumber zat
pengatur tumbuh alami berpengaruh nyata terhadap
variabel bobot kering total. Berdasarkan uji lanjut
Dunnet (Tabel 4.13), hasilnya juga berbeda nyata baik
pada umur tebu 40, 80, ataupun 120 hst. Pada umur tebu
40 hst, pemberian air kelapa muda 25 %, air kelapa
muda 50 %, air kelapa muda 75 %, dan urin sapi perah
25 % mampu menghasilkan nilai bobot kering total yang
lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol (tanpa bahan
organik). Peningkatan konsentrasi urin sapi perah
hingga 50-75 % justru menghasilkan nilai bobot kering
total yang lebih rendah dan tidak berbeda nyata dengan
kontrol (tanpa bahan organik), sedangkan untuk
perlakuan ekstrak kecambah kacang hijau 25 %, ekstrak
60
kecambah kacang hijau 50 %, dan ekstrak kecambah
kacang hijau 75 %, nilai bobot kering total bibit tebu
yang dihasilkan tidak berbeda nyata jika dibandingkan
dengan kontrol (tanpa bahan organik) walaupun terlihat
adanya kecenderungan penurunan nilai bobot kering
total seiring dengan penambahan konsentrasi pada
masing-masing bahan organik.
Pada umur tebu 80 dan 120 hst, pemberian air
kelapa muda 25 % dan urin sapi perah 25 % secara nyata
mampu menghasilkan nilai bobot kering total yang lebih
tinggi dibandingkan kontrol (tanpa bahan organik).
Penambahan konsentrasi air kelapa muda dan urin sapi
perah hingga 50-75 % justru menurunkan nilai bobot
kering total bibit tebu dan tidak berbeda nyata dengan
kontrol (tanpa bahan organik). Sama halnya dengan
perlakuan ekstrak kecambah kacang hijau baik pada
konsentrasi 25, 50, ataupun 75 %, bobot kering total
yang dihasilkan tidak berbeda nyata dengan perlakuan
tanpa bahan organik.
14.Nisbah Akar Tajuk
Tabel 4.14. Pengaruh macam dan konsentrasi bahanorganik sebagai sumber zat pengatur tumbuhalami terhadap nisbah akar tajuk bibit tebu
Perlakuan Nisbah Akar Tajuk40 hst 80 hst 120 hst
Kontrol 0,37 0,72 1,43
Air kelapa muda 25 % 0,69 ns
0,72 ns
1,42 ns
Air kelapa muda 50 % 0,57 0,80 1,58 61
ns ns ns
Air kelapa muda 75 % 0,95 ns
0,73 ns
1,44 ns
Urin sapi perah 25 % 0,40 ns
1,01 ns
1,98 ns
Urin sapi perah 50 % 1,00 ns
0,47 ns
0,93 ns
Urin sapi perah 75 % 0,21 ns
0,62 ns
1,23 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 25 %
0,47 ns
0,79 ns
1,61 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 50 %
0,19 ns
0,93 ns
1,85 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 75 %
0,20 ns
0,59 ns
1,17 ns
Keterangan: ns = tidak berbeda nyata dengan kontrol, * =berbeda nyata dengan kontrol
Nisbah akar tajuk merupakan perbandingan antara
bobot kering akar dan bobot kering tajuk. Apabila
angka yang dihasilkan lebih dari satu berarti akar
memiliki bobot kering yang lebih berat dibandingkan
tajuk. Sebaliknya, apabila angka yang dihasilkan
kurang dari satu berarti tajuk memiliki bobot kering
yang lebih berat daripada akar. Jika angka yang
dihasilkan sama dengan satu artinya tajuk dan akar
memiliki bobot kering yang seimbang. Nisbah akar tajuk
memiliki kepentingan fisiologis karena dapat
menggambarkan salah satu tipe dari kekeringan.
Meskipun nisbah akar tajuk dikendalikan secara
genetis, nisbah akar tajuk juga sangat dipengaruhi
oleh lingkungan yang kuat (Gardner et al., 1991).
Analisis varian menunjukkan hasil yang tidak
berbeda nyata pada perlakuan macam dan konsentrasi
62
bahan organik sebagai sumber zat pengatur tumbuh alami
terhadap nisbah akar tajuk bibit tebu baik pada umur
40, 80, ataupun 120 hst (Tabel 4.14). Perlakuan air
kelapa muda 25 %, air kelapa muda 50 %, air kelapa
muda 75 %, urin sapi perah 25 %, urin sapi perah 50 %,
urin sapi perah 75 %, ekstrak kecambah kacang hijau 25
%, ekstrak kecambah kacang hijau 50 %, dan ekstrak
kecambah kacang hijau 75 % tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap variabel nisbah akar tajuk bibit
tebu.
15.Jumlah Ruas
Tabel 4.15. Pengaruh macam dan konsentrasi bahanorganik sebagai sumber zat pengatur tumbuhalami terhadap jumlah ruas bibit tebu
Perlakuan Jumlah Ruas12 mst 17 mst
Kontrol 2,40 3,60Air kelapa muda 25 % 3,00 ns 4,60 nsAir kelapa muda 50 % 2,80 ns 4,00 nsAir kelapa muda 75 % 2,80 ns 3,80 nsUrin sapi perah 25 % 2,80 ns 4,00 nsUrin sapi perah 50 % 2,60 ns 3,80 nsUrin sapi perah 75 % 2,60 ns 3,60 nsEkstrak kecambah kacang hijau 25 % 2,80 ns 3,80 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 50 % 2,60 ns 3,60 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 75 % 2,40 ns 3,60 nsKeterangan: ns = tidak berbeda nyata dengan kontrol, * =
berbeda nyata dengan kontrol
Jumlah ruas tunas diketahui dengan menghitung
seluruh ruas tunas dari dasar hingga ujung.63
Berdasarkan hasil analisis varian (Tabel 4.15),
diketahui bahwa perlakuan macam dan konsentrasi bahan
organik sebagai sumber zat pengatur tumbuh alami tidak
berpengaruh secara nyata terhadap jumlah ruas bibit
tebu baik pada umur 6, 12, maupun 17 mst. Pada umur 6
mst, ruas tebu belum terbentuk. Hal ini sesuai dengan
yang dikatakan Lukito (2008), yaitu bahwa pembentukan
ruas tebu berlangsung pada umur tanaman antara 3-9
bulan.
16.Diameter Tunas
Tabel 4.16. Pengaruh macam dan konsentrasi bahanorganik sebagai sumber zat pengatur tumbuhalami terhadap diameter tunas bibit tebu
Perlakuan Diameter Tunas (cm)6 mst 12 mst 17 mst
Kontrol 0,77 2,38 3,58Air kelapa muda 25 % 1,18 * 2,83 * 4,25 *
Air kelapa muda 50 % 1,04 * 2,61 ns
3,93 ns
Air kelapa muda 75 % 1,01 * 2,46 ns
3,70 ns
Urin sapi perah 25 % 0,95 ns
2,53 ns
3,81 ns
Urin sapi perah 50 % 0,91 ns
2,35 ns
3,54 ns
Urin sapi perah 75 % 0,88 ns
2,23 ns
3,36 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 25 %
0,89 ns
2,53 ns
3,80 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 50 %
0,71 ns
2,37 ns
3,56 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 75 %
0,58 ns
2,17 ns
3,26 ns
Keterangan: ns = tidak berbeda nyata dengan kontrol, * =berbeda nyata dengan kontrol
64
Hasil analisis varian menunjukkan bahwa pemberian
bahan organik sebagai sumber zat pengatur tumbuh alami
berpengaruh nyata terhadap variabel diameter tunas.
Berdasarkan uji lanjut Dunnet (Tabel 4.16), perbedaan
nyata ditunjukkan baik pada umur tebu 6, 12, maupun 17
mst. Pada umur tebu 6 mst, pemberian air kelapa muda
25, 50, dan 75 % secara nyata mampu menghasilkan
diameter tunas bibit tebu yang lebih besar
dibandingkan kontrol (tanpa bahan organik) walaupun
terlihat adanya kecenderungan penurunan nilai diameter
tunas seiring dengan penambahan konsentrasi air kelapa
muda, sedangkan untuk perlakuan urin sapi perah dan
ekstrak kecambah kacang hijau baik pada konsentrasi
25, 50, ataupun 75 %, hasilnya tidak berbeda nyata
dengan kontrol (tanpa bahan organik) walaupun terlihat
adanya kecenderungan penurunan nilai diameter tunas
seiring dengan penambahan konsentrasi pada masing-
masing bahan organik.
Pada umur tebu 12 dan 17 mst, perlakuan air kelapa
muda 25 % mampu menghasilkan diameter tunas yang lebih
besar dibandingkan dengan perlakuan tanpa bahan
organik. Peningkatan konsentrasi air kelapa muda
hingga 50-75 % justru menghasilkan diameter tunas yang
lebih kecil dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan
tanpa bahan organik. Begitu juga dengan perlakuan
lainnya, yaitu perlakuan urin sapi perah dan ekstrak
kecambah kacang hijau baik pada konsentrasi 25, 50,65
ataupun 75 %, hasilnya tidak berbeda nyata dengan
perlakuan tanpa bahan organik. Meski nampak adanya
kecenderungan penurunan nilai diameter tunas seiring
dengan penambahan konsentrasi pada masing-masing bahan
organik, pemberian air kelapa muda 50 %, air kelapa
muda 75 %, urin sapi perah 25 %, urin sapi perah 50 %,
urin sapi perah 75 %, ekstrak kecambah kacang hijau 25
%, ekstrak kecambah kacang hijau 50 %, dan ekstrak
kecambah kacang hijau 75 % secara signifikan tidak
mampu meningkatkan nilai diameter tunas bibit tebu
jika dibandingkan dengan perlakuan tanpa bahan
organik.
17.Panjang Ruas
Tabel 4.17. Pengaruh macam dan konsentrasi bahanorganik sebagai sumber zat pengatur tumbuhalami terhadap panjang ruas bibit tebu
Perlakuan Panjang Ruas (cm)12 mst 17 mst
Kontrol 9,81 13,90Air kelapa muda 25 % 12,00 ns 17,01 nsAir kelapa muda 50 % 11,77 ns 16,67 nsAir kelapa muda 75 % 11,53 ns 16,34 nsUrin sapi perah 25 % 10,83 ns 15,34 nsUrin sapi perah 50 % 10,54 ns 14,94 ns
Urin sapi perah 75 % 9,47 ns 13,41 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 25 % 10,30 ns 14,59 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 50 % 10,07 ns 14,26 ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 75 %
9,02 ns 12,78 ns
66
Keterangan: ns = tidak berbeda nyata dengan kontrol, * =berbeda nyata dengan kontrol
Hasil analisis varian menunjukkan tidak terdapat
pengaruh yang signifikan pada perlakuan macam dan
konsentrasi bahan organik sebagai sumber zat pengatur
tumbuh alami terhadap panjang ruas tebu baik pada umur
6, 12, ataupun 17 mst (Tabel 4.17). Panjang ruas tebu
pada umur 12 mst rata-rata berkisar 9-12 cm, sedangkan
panjang ruas tebu pada umur 17 mst rata-rata berkisar
12-17 cm.
Pada umur 6 mst, ruas tebu belum terbentuk. Proses
pemanjangan batang adalah proses yang paling dominan
pada fase pertumbuhan tebu. Selama fase ini
berlangsung, pembentukan ruas tebu terjadi sebanyak 3-
4 ruas per bulan dan jumlah ini akan menurun dengan
bertambahnya umur (tua). Fase ini berlangsung pada
umur tanaman antara 3-9 bulan (Lukito, 2008).
18.Tinggi Tunas
Tabel 4.18. Pengaruh macam dan konsentrasi bahanorganik sebagai sumber zat pengatur tumbuhalami terhadap tinggi tunas bibit tebu
Perlakuan Tinggi tunas (cm)6 mst 12 mst 17 mst
Kontrol 119,00 175,54 207,44
Air kelapa muda 25 % 150,00 *
197,86 *
233,86*
Air kelapa muda 50 % 146,26 *
191,02 ns
225,78ns
Air kelapa muda 75 % 138,32 ns
184,40 ns
217,94ns
67
Urin sapi perah 25 % 129,20 ns
186,16 ns
220,02ns
Urin sapi perah 50 % 131,14 ns
177,28 ns
209,56ns
Urin sapi perah 75 % 117,04 ns
174,22 ns
205,90ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 25 %
127,10 ns
183,76 ns
217,20ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 50 %
114,60 ns
176,14 ns
208,20ns
Ekstrak kecambah kacang hijau 75 %
102,20 ns
172,06 ns
203,40ns
Keterangan: ns = tidak berbeda nyata dengan kontrol, * =berbeda nyata dengan kontrol
Hasil analisis varian menunjukkan bahwa pemberian
bahan organik sebagai sumber zat pengatur tumbuh alami
berpengaruh nyata terhadap variabel tinggi tunas.
Berdasarkan uji lanjut Dunnet (Tabel 4.18), hasilnya
juga berbeda nyata baik pada umur tebu 6, 12, maupun
17 mst. Pada umur tebu 6 mst, pemberian air kelapa
muda 25 % dan 50 % secara nyata mampu menghasilkan
tunas tebu yang lebih tinggi dibandingkan kontrol
(tanpa bahan organik). Penambahan konsentrasi air
kelapa muda hingga 75 % justru menurunkan nilai tinggi
tunas bibit dan tidak berbeda nyata dengan kontrol
(tanpa bahan organik). Sama halnya dengan perlakuan
urin sapi perah dan ekstrak kecambah kacang hijau baik
pada konsentrasi 25, 50, ataupun 75 %, tinggi tunas
yang dihasilkan tidak berbeda nyata dengan kontrol
(tanpa bahan organik) walaupun terlihat adanya
kecenderungan penurunan nilai tinggi tunas seiring
68
dengan penambahan konsentrasi pada masing-masing bahan
organik.
Pada umur tebu 12 dan 17 mst, perlakuan air kelapa
muda 25 % juga mampu menghasilkan tanaman yang lebih
tinggi dibandingkan dengan kontrol (tanpa bahan
organik). Peningkatan konsentrasi air kelapa muda
hingga 50-75 % justru menghasilkan tunas tebu yang
lebih pendek dan tidak berbeda nyata dengan kontrol
(tanpa bahan organik). Begitu juga dengan perlakuan
lainnya, yaitu perlakuan urin sapi perah dan ekstrak
kecambah kacang hijau baik pada konsentrasi 25, 50,
ataupun 75 %, hasilnya tidak berbeda nyata dengan
kontrol (tanpa bahan organik). Jadi, dapat dikatakan
bahwa perlakuan air kelapa muda 50 %, air kelapa muda
75 %, urin sapi perah 25 %, urin sapi perah 50 %, urin
sapi perah 75 %, ekstrak kecambah kacang hijau 25 %,
ekstrak kecambah kacang hijau 50 %, dan ekstrak
kecambah kacang hijau 75 % baik pada umur 12 maupun
17 mst secara signifikan tidak mampu meningkatkan
nilai tinggi tunas bibit tebu bila dibandingkan dengan
kontrol (tanpa bahan organik) walaupun terlihat adanya
kecenderungan penurunan nilai tinggi tunas seiring
dengan penambahan konsentrasi pada masing-masing bahan
organik.
C. Pembahasan Umum
69
Zat pengatur tumbuh dengan macam dan konsentrasi yang
sesuai berpotensi untuk meningkatkan persentase
keberhasilan pembibitan. Selain itu, dapat juga
mempercepat pembentukan dan pertumbuhan akar serta tunas
yang berasal dari bahan stek. Proses pertunasan tebu
biasanya diawali dengan aktivitas imbibisi, yaitu
aktivitas masuk dan terserapnya (absorpsi) air ke dalam
bahan tanam. Kelembaban tanah pada kapasitas lapangan
sangat mendukung proses ini. Menurut Gardner (1991),
hidrasi jaringan akan terjadi setelah aktivitas imbibisi
berlangsung. Selanjutnya akan terjadi absorpsi oksigen,
pengaktifan dan reaksi enzim, transpor molekul yang
terhidrolisis, peningkatan respirasi dan asimilasi,
inisiasi pembelahan dan pembesaran sel, dan akhirnya
terjadi pemunculan tunas. Menurut Leopold (1955), mata
tunas pada stek sangat diperlukan untuk mendorong
terjadinya perakaran stek. Pembentukan akar tidak akan
terjadi bila mata tunas dihilangkan atau dalam keadaan
dorman. Hal ini terjadi karena tunas berperan sebagai
sumber auksin yang menstimulir pembentukan akar, terutama
bila mata tunas mulai tumbuh. Menurut Hartmann dan Kester
(1975), IAA diidentifikasikan sebagai senyawa alami yang
menunjukkan aktivitas auksin yang mendorong pembentukan
akar adventif.
Setiap variabel pengamatan dinyatakan saling
berkorelasi satu sama lain jika sifatnya nyata. Korelasi
dapat bersifat positif ataupun negatif. Tabel 4.19
70
memberi informasi bahwa volume akar berkorelasi positif
dengan jumlah dan luas daun secara sangat nyata. Volume
akar bibit tebu yang semakin besar secara sangat nyata
akan diikuti oleh pertambahan jumlah dan luas daun pada
bibit tebu tersebut. Namun, pertambahan nilai pada
variabel panjang akar utama tidak diikuti oleh
pertambahan nilai pada variabel volume akar, jumlah daun,
dan luas daun bibit tebu. Hal ini diduga terjadi karena
perakaran yang terdapat pada tebu merupakan perakaran
serabut. Pada perakaran serabut, akar primer tidak dapat
bertahan lama dalam pertumbuhan tanaman dan segera
mengering, lalu dari pangkal akar tersebut akan muncul
akar baru yang disebut akar adventif.
Tabel 4.19. Nilai koefisien korelasi antara variabelpanjang akar utama, volume akar, jumlah daun, danluas daun bibit tebu
VariabelPanjangAkarUtama
Volume Akar
Jumlah Daun
Luas Daun
Panjang Akar Utama 1
Volume Akar 0,160 1Jumlah Daun 0,063 0,376 ** 1Luas Daun 0,119 0,446 ** 0,458 ** 1Keterangan: Tanda (*) menunjukkan adanya korelasi yang nyata
antar variabel pengamatan pada tingkat kepercayaan 5%.Tanda (**) menunjukkan adanya korelasi yang sangat nyataantar variabel pengamatan pada tingkat kepercayaan 5%.
Secara umum, stek tebu yang mendapatkan perlakuan air
kelapa muda 25 % volume akarnya lebih besar daripada
perlakuan lainnya. Volume akar yang lebih besar
menyebabkan kapasitas akar dalam menyerap air dan nutrisi
71
juga lebih kuat sehingga jumlah air dan nutrisi yang
ditranslokasikan menuju daun lebih banyak, terutama pada
bibit tebu yang mendapatkan perlakuan air kelapa muda 25
%. Akar-akar adventif ini yang mempengaruhi nilai volume
akar. Pasokan air dan nutrisi tanaman yang lebih kuat
menyebabkan daun pada stek tebu yang mendapatkan
perlakuan air kelapa muda 25 % jumlahnya lebih banyak
serta lebih luas jika dibandingkan dengan stek tebu yang
mendapatkan perlakuan lainnya.
Pada Tabel 4.19, nampak bahwa jumlah daun berkorelasi
positif secara sangat nyata dengan luas daun. Jumlah daun
yang semakin bertambah akan menyebabkan luas daun yang
semakin bertambah pula. Jumlah daun yang lebih banyak
dengan luasan per daun yang sama besar merupakan penyebab
utama lebih luasnya daun per bibit tebu. Berdasarkan
penelitian, bibit tebu yang mendapatkan perlakuan air
kelapa muda 25 % daunnya lebih luas daripada perlakuan
lainnya. Menurut Gardner et al. (1991), tanaman cenderung
menginvestasikan sebagian besar awal pertumbuhan dalam
bentuk penambahan luas daun.
Akar berperan dalam penyerapan air dan hara dari
dalam tanah. Semakin besar nilai volume akar, maka
semakin terpenuhi kebutuhan hara dan air bagi tanaman
karena meningkatnya kapasitas akar dalam penyerapan air
maupun hara. Apabila kebutuhan air dan hara bagi tanaman
tercukupi dengan optimal maka proses fotosintesis dapat
berjalan dengan baik. Hasil fotosintesis tersebut
72
selanjutnya ditranslokasikan ke seluruh organ tanaman,
termasuk daun, untuk menunjang aktivitas pertumbuhan
daun. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Rogomulyo
(1992), yaitu bahwa akar merupakan organ yang menentukan
kelangsungan hidup suatu tanaman. Semakin cepat dan
banyak akar terbentuk, maka semakin besar kemungkinan
bibit tumbuh sehat dan kuat.
Tabel 4.20. Nilai koefisien korelasi antara variabelluas daun dan laju asimilasi bersih bibit tebu
Variabel Luas Daun Laju AsimilasiBersih
Luas Daun 1Laju Asimilasi Bersih 0,460 ** 1Keterangan: Tanda (*) menunjukkan adanya korelasi yang nyata
antar variabel pengamatan pada tingkat kepercayaan 5%.Tanda (**) menunjukkan adanya korelasi yang sangat nyataantar variabel pengamatan pada tingkat kepercayaan 5%.
Pada Tabel 4.20, luas daun diketahui berkorelasi
positif secara sangat nyata dengan laju asimilasi bersih
per luas daun total. Artinya bahwa pertambahan luas daun
akan selalu diikuti oleh peningkatan laju asimilasi
bersih per luas daun total. Laju asimilasi bersih
merupakan ukuran efisiensi daun dalam menghasilkan bahan
kering dan secara langsung dipengaruhi oleh kemampuan
daun dalam menyerap radiasi matahari dan hara. Daun
berfungsi sebagai organ utama fotosintesis. Jaringan
fotosintesis yang hijau (klorofil) pada daun secara
efisien dapat menyerap radiasi matahari yang dibutuhkan
oleh tanaman (Gardner et al., 1991). Semakin besar nilai
luas daun, maka akan semakin meningkat pula kapasitas73
daun untuk melakukan fotosintesis. Apabila semakin banyak
daun yang dapat melakukan fotosintesis dengan baik, maka
akan semakin banyak pula fotosintat yang dihasilkan.
Fotosintat ini selanjutnya ditranslokasikan ke seluruh
organ tanaman untuk dimanfaatkan dalam proses pertumbuhan
dan perkembangan sesuai dengan fase pertumbuhannya.
Berdasarkan hasil penelitian, bibit tebu yang mendapatkan
perlakuan air kelapa muda 25 % daunnya lebih luas jika
dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Daun yang lebih
luas dengan laju asimilasi bersih per satuan luas daun
yang sama besar merupakan penyebab utama lebih besarnya
nilai laju asimilasi bersih per luas daun total suatu
bibit tebu.
Tabel 4.21. Nilai koefisien korelasi antara variabellaju asimilasi bersih dan laju pertumbuhan nisbibibit tebu
Variabel Laju AsimilasiBersih
Laju PertumbuhanNisbi
Laju Asimilasi Bersih 1
Laju Pertumbuhan Nisbi 0,452 ** 1Keterangan: Tanda (*) menunjukkan adanya korelasi yang nyata
antar variabel pengamatan pada tingkat kepercayaan 5%.Tanda (**) menunjukkan adanya korelasi yang sangat nyataantar variabel pengamatan pada tingkat kepercayaan 5%.
Tabel 4.21 menunjukkan adanya korelasi positif secara
sangat nyata antara laju asimilasi bersih dengan laju
pertumbuhan nisbi. Semakin tinggi laju asimilasi bersih,
maka secara sangat nyata akan semakin tinggi juga laju
pertumbuhan nisbi. Keduanya memang berperan dalam
74
pembentukan bobot kering tanaman. Laju asimilasi bersih
menunjukkan kemampuan tanaman untuk menyediakan asimilat
melalui proses fotosintesis selama pertumbuhannya
ditentukan oleh kemampuan per satuan luas daun dan luas
daun total. Nilai laju asimilasi bersih yang tinggi
menunjukkan bahwa sebagian besar daun mampu menyerap
radiasi matahari dan hara untuk berfotosintesis secara
optimal. Semakin tinggi hasil fotosintesis, berarti
semakin besar pertambahan bahan kering tanaman.
Pertambahan bahan kering tanaman ini yang biasanya
disebut dengan laju pertumbuhan nisbi.
Tabel 4.22. Nilai koefisien korelasi antara variabellaju pertumbuhan nisbi, bobot kering akar, bobotkering tajuk, dan bobot kering total bibit tebu
Variabel
LajuPertumbu
hanNisbi
BobotKeringAkar
BobotKeringTajuk
BobotKeringTotal
Laju Pertumbuhan Nisbi 1
Bobot Kering Akar 0,337 * 1
Bobot Kering Tajuk 0,146 0,412
** 1
Bobot Kering Total
0,299 *
0,901** 0,803 ** 1
Keterangan: Tanda (*) menunjukkan adanya korelasi yang nyataantar variabel pengamatan pada tingkat kepercayaan 5%.Tanda (**) menunjukkan adanya korelasi yang sangat nyataantar variabel pengamatan pada tingkat kepercayaan 5%.
Berdasarkan nilai koefisien korelasi pada Tabel 4.22,
diketahui bahwa terdapat korelasi positif yang nyata pada
variabel laju pertumbuhan nisbi dengan bobot kering akar
75
dan bobot kering total. Korelasi positif secara sangat
nyata terdapat pada variabel bobot kering tajuk dengan
bobot kering total, bobot kering akar dengan bobot kering
tajuk, dan bobot kering akar dengan bobot kering total.
Hal ini berarti pertambahan nilai pada variabel bobot
kering akar secara sangat nyata akan diikuti oleh
pertambahan nilai pada variabel bobot kering tajuk dan
bobot kering total. Pertambahan nilai pada variabel bobot
kering tajuk secara sangat nyata akan diikuti oleh
pertambahan nilai pada variabel bobot kering total.
Begitu juga untuk pertambahan nilai pada variabel laju
pertumbuhan nisbi, secara nyata akan diikuti dengan
pertambahan nilai pada variabel bobot kering akar dan
bobot kering total. Berdasarkan nilai koefisien korelasi
antara variabel laju pertumbuhan nisbi dan bobot kering
tajuk, diketahui bahwa tidak ada korelasi nyata antar
keduanya. Artinya bahwa peningkatan laju pertumbuhan
nisbi tidak selalu diikuti dengan peningkatan bobot
kering tajuk. Hal ini diduga terjadi karena kecepatan
pertambahan luas daun lebih tinggi dibandingkan dengan
kecepatan pertambahan bobot kering, atau dapat juga
terjadi karena hasil bersih asimilat pada umur tertentu
cenderung lebih banyak disebarkan ke akar untuk
pertumbuhan dan perkembangannya.
Bobot kering total dipengaruhi oleh laju pertumbuhan
nisbi. Laju pertumbuhan nisbi merupakan pertambahan bahan
kering tanaman. Semakin tinggi pertambahan bahan kering
76
tanaman sebagai hasil bersih dari proses fotosintesis,
maka akan semakin besar bobot kering total tanaman.
Berdasarkan Tabel 4.13, bibit tebu yang diberi perlakuan
air kelapa muda 25 % memiliki bobot kering total yang
lebih besar dibandingkan dengan perlakuan lainnya,
kecuali perlakuan urin sapi perah 25 %. Bobot kering
total yang lebih besar ini menggambarkan lebih banyaknya
hasil bersih asimilat yang ditranslokasikan ke seluruh
tubuh tanaman untuk pertumbuhan, perkembangan, cadangan
makanan, dan pengelolaan sel.
Gambar 4.1 menunjukkan hubungan antara konsentrasi
air kelapa muda dan bobot kering total bibit tebu.
Berdasarkan analisis regresi, diketahui bahwa konsentrasi
optimum dari air kelapa muda berada sekitar 38,70 %. Hal
ini berarti peningkatan konsentrasi air kelapa muda
hingga sekitar 38,70 % mampu meningkatkan bobot kering
total bibit tebu. Apabila konsentrasi optimum ini terus
dinaikkan, maka bobot kering total tanaman bibit tebu
justru akan semakin menurun. Nilai koefisien determinasi
(R2) adalah 0,7436. Artinya bahwa peningkatan konsentrasi
bahan organik sebagai sumber zat pengatur tumbuh alami
berpengaruh cukup besar terhadap peningkatan bobot kering
total bibit tebu.
77
Gambar 4.1. Grafik regresi antarakonsentrasi air kelapa muda dan bobotkering total bibit tebu berumur 120 hst
Grafik regresi antara konsentrasi urin sapi perah dan
bobot kering total bibit tebu berumur 120 hst (Gambar
4.2) menunjukkan bahwa konsentrasi optimum dari urin sapi
perah berada pada sekitar angka 34,44 berdasarkan
analisis regresi. Artinya bahwa peningkatan konsentrasi
urin sapi perah hingga sekitar 34,44 % mampu meningkatkan
bobot kering total bibit tebu. Bobot kering total bibit
tebu akan semakin menurun jika konsentrasi optimum ini
terus ditingkatkan. Pada grafik terlihat nilai koefisien
determinasi (R2) sebesar 0,532. Hal ini berarti
peningkatan nilai bobot kering total bibit tebu cukup
dipengaruhi oleh peningkatan konsentrasi bahan organik
sebagai sumber zat pengatur tumbuh alami.
78
Gambar 4.2. Grafik regresi antarakonsentrasi urin sapi perah dan bobot
kering total bibit tebu berumur 120 hst
Pada Tabel 4.23, terlihat bahwa variabel bobot kering
tajuk berkorelasi positif secara nyata dengan variabel
panjang ruas. Artinya bahwa secara nyata peningkatan
nilai bobot kering tajuk akan diikuti oleh peningkatan
nilai pada variabel panjang ruas. Tabel 4.23 juga
menunjukkan adanya korelasi positif yang sangat nyata
pada variabel bobot kering tajuk dengan variabel diameter
dan tinggi tunas. Hal ini berarti bahwa peningkatan bobot
kering tajuk akan diikuti oleh pertambahan diameter dan
tinggi tunas secara sangat nyata. Pada variabel diameter
tunas, secara sangat nyata pertambahan nilainya akan
diikuti dengan pertambahan nilai pada variabel panjang
ruas dan tinggi tunas. Sama halnya dengan variabel
panjang ruas dan tinggi tunas, tingginya tunas
dipengaruhi secara sangat nyata oleh panjangnya ruas.
79
Bobot kering tajuk merupakan hasil bersih asimilat
yang ditranslokasikan ke bagian tajuk bibit untuk
menunjang aktivitas pertumbuhan tajuk (tunas dan daun).
Pada hasil penelitian, diketahui bahwa bibit tebu yang
diberi perlakuan air kelapa muda 25 % memiliki diameter
tunas dan panjang ruas yang nilainya lebih tinggi
dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Tunas yang
diameternya lebih besar dan ruasnya lebih panjang ini
menggambarkan banyaknya hasil bersih asimilat yang
ditranslokasikan ke bagian tersebut. Panjangnya ruas pada
tunas dapat menyebabkan tunas bibit tebu menjadi semakin
tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang
menunjukkan bahwa tunas yang lebih tinggi juga dimiliki
oleh bibit tebu yang diberi perlakuan air kelapa muda 25
% (Tabel 4.18).
Tabel 4.23. Nilai koefisien korelasi antara variabelbobot kering tajuk, diameter tunas, panjang ruas,dan tinggi tunas bibit tebu
VariabelBobotKeringTajuk
DiameterTunas
PanjangRuas
TinggiTunas
Bobot Kering Tajuk 1
Diameter Tunas 0,521 ** 1
Panjang Ruas 0,315 * 0,597 ** 1
Tinggi Tunas 0,451 ** 0,559 ** 0,558 ** 1
Keterangan: Tanda (*) menunjukkan adanya korelasi yang nyataantar variabel pengamatan pada tingkat kepercayaan 5%.Tanda (**) menunjukkan adanya korelasi yang sangat nyataantar variabel pengamatan pada tingkat kepercayaan 5%.
80
Grafik regresi antara konsentrasi air kelapa muda dan
tinggi tunas bibit tebu berumur 17 mst (Gambar 4.3)
menunjukkan bahwa konsentrasi optimum dari air kelapa
muda berada sekitar 40,89 % berdasarkan analisis regresi.
Hal ini berarti peningkatan konsentrasi air kelapa muda
hingga sekitar 40,89 % mampu meningkatkan tinggi tunas
bibit tebu. Apabila konsentrasi optimum ini terus
dinaikkan, maka tinggi tunas bibit tebu justru akan
semakin menurun. Nilai koefisien determinasi (R2) adalah
0,841. Jadi, peningkatan konsentrasi bahan organik
sebagai sumber zat pengatur tumbuh alami cukup
berpengaruh besar terhadap peningkatan tinggi tunas bibit
tebu.
Gambar 4.3. Hubungan regresi antarakonsentrasi air kelapa muda dengan tinggi
tunas bibit tebu berumur 17 mst
Berdasarkan hasil penelitian, perlakuan air kelapa
muda 25 % mampu meningkatkan tinggi tunas, jumlah daun,
81
diameter tunas, bobot segar akar, bobot segar tajuk,
bobot segar total, bobot kering akar, bobot kering tajuk,
bobot kering total, volume akar, dan luas daun bibit tebu
jika dibandingkan dengan kontrol (tanpa bahan organik).
Berdasarkan hasil tersebut, diduga dalam air kelapa muda
terkandung sitokinin yang berperan dalam pembelahan sel.
Hal ini didukung oleh pendapat Rineksane (2000) yang
menyatakan bahwa cairan endosperma dari buah kelapa
diyakini mampu menyediakan sitokinin alami yang aktif.
Zat ini disinyalir mampu menginduksi pembentukan akar dan
tunas dengan cara meningkatkan metabolisme asam nukleik
dan sintesis protein.
Pada dasarnya, sitokinin tidak mampu menjalankan
fungsinya dengan baik secara tunggal. Sitokinin dapat
berperan secara aktif dalam proses pembentukan tunas
apabila bekerja sama dengan auksin. Seperti yang
diungkapkan Widiastoety et al. (1997), yaitu bahwa
pembentukan tunas dan diferensiasi berlangsung jika
terdapat interaksi antara auksin dan sitokinin, dengan
konsentrasi sitokinin yang lebih besar. Berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2005), terdapat
kandungan auksin (0,237 ppm IAA), sitokinin (0,441 ppm
kinetin dan 0,247 ppm zeatin), dan giberelin (0,460 ppm
GA3; 0,255 ppm GA5; 0,053 ppm GA7) dalam air kelapa muda.
Angka-angka tersebut memberikan pengaruh yang baik bagi
pembentukan dan pertumbuhan tunas tebu.
82
Berdasarkan fungsinya, auksin berperan dalam
pembesaran dan pemanjangan sel. Di dalam sel, auksin
memacu protein tertentu yang ada di membran plasma untuk
memompa ion H+ ke dinding sel. Ion H+ ini mengaktifkan
enzim tertentu, sehingga memutuskan beberapa ikatan
silang hidrogen rantai molekul selulosa penyusun dinding
sel. Hal ini mengakibatkan dinding sel melunak dan
permeabilitasnya meningkat karena substansi pektin telah
dilemahkan, sehingga akan memudahkan masuknya air ke
dalam sel (imbibisi) yang merupakan aktivitas awal dari
proses pertunasan. Walaupun telah dilemahkan, sel ini
tidak akan rusak karena sel ini akan terus tumbuh dengan
mensintesis kembali material dinding sel dan sitoplasma,
sedangkan untuk proses pengaktifan enzim yang
mengakibatkan terjadinya reaksi enzimatik di dalam bahan
tanam, diperankan oleh giberelin (Wilkins, 1989). Reaksi
enzimatik ini berkaitan dengan proses perombakan cadangan
makanan, seperti karbohidrat dan protein, yang diperlukan
untuk pembentukan tunas.
Menurut Danarto (2008), urin sapi perah mengandung
hormon yang bisa memacu pertumbuhan tanaman, seperti
auksin (IAA), sitokinin (kinetin), dan giberelin (GA).
Sapi perah memakan lebih banyak hijauan daripada sapi
potong sehingga kandungan auksin hijauan dapat
disekresikan lewat urin. Secara umum, kandungan auksin
pada urin sapi lebih besar daripada kandungan auksin pada
air kelapa muda. Auksin yang terkandung dalam urin sapi
83
betina sekitar 1852 ppm, sedangkan kandungan auksin pada
air kelapa muda hanya sekitar 0,237 ppm. Namun pada
sebagian besar variabel pertumbuhan, kandungan ini tidak
membuat perlakuan urin sapi perah menjadi lebih baik
dibandingkan perlakuan air kelapa muda, terutama pada
konsentrasi tinggi. Seperti yang terdapat pada variabel
waktu muncul tunas, perlakuan ini cenderung menghasilkan
waktu pertunasan yang lebih lama dibandingkan dengan
perlakuan air kelapa muda baik pada konsentrasi 25, 50,
ataupun 75 % (Tabel 4.1). Menurut Sriyanti (2000), auksin
dapat merangsang pertumbuhan akar pada konsentrasi rendah
(sesuai kebutuhan tanaman), sedangkan pada konsentrasi
tinggi, justru akan menghambat laju pemanjangan koleoptil
(ujung akar) dan batang akibat mulai hilangnya tekanan
turgor pada dinding sel. Selain itu, hasil yang tidak
lebih baik juga dapat terjadi karena diduga kandungan
auksin eksogen yang tinggi belum mampu merangsang kinerja
auksin endogen dengan baik akibat terjadinya persaingan
pada tempat kedudukan penerima. Gardner et al. (2008)
mengatakan bahwa kandungan yang tinggi memungkinkan
terjadinya penempatan molekul yang hanya melekat sebagian
pada tempat kedudukan penerima. Hal ini mengakibatkan
kurang efektifnya gabungan tersebut.
Apabila ditilik secara keseluruhan, terdapat pengaruh
nyata pada perlakuan macam dan konsentrasi bahan organik
sebagai sumber zat pengatur tumbuh alami terhadap
sebagian besar variabel pertumbuhan bibit tebu, seperti
84
tinggi tunas, jumlah daun, diameter tunas, bobot segar
akar, bobot segar tajuk, bobot segar total, bobot kering
akar, bobot kering tajuk, bobot kering total, volume
akar, dan luas daun. Nilai tertinggi sebagian besar
variabel pengamatan tersebut secara signifikan terdapat
pada perlakuan air kelapa muda 25 % yang cenderung tidak
berbeda nyata dengan perlakuan air kelapa muda 50 % dan
urin sapi perah 25 %, sedangkan untuk perlakuan urin sapi
perah 50 %, urin sapi perah 75 %, ekstrak kecambah kacang
hijau 25 %, ekstrak kecambah kacang hijau 50 %, dan
ekstrak kecambah kacang hijau 75 %, tidak terdapat
perbedaan yang nyata pada setiap variabel pertumbuhan
bibit tebu jika dibandingkan dengan perlakuan tanpa bahan
organik. Perlakuan air kelapa muda 75 % yang berbeda
nyata dan lebih baik daripada kontrol hanya nampak pada
variabel bobot kering total bibit tebu pada umur 40 hst.
Pada variabel dan umur tebu lainnya, perlakuan air kelapa
muda 75 % tidak berbeda nyata dengan kontrol. Hal ini
dapat terjadi diduga karena konsentrasi air kelapa muda
yang digunakan terlalu tinggi. Menurut Fauzi et al. (1989),
penggunaan zat pengatur tumbuh yang berlebihan akan
bersifat meracun yang mengakibatkan pertumbuhan stek
terhambat, bahkan mengakibatkan kegagalan tumbuhnya stek.
Hormon dengan konsentrasi rendah dapat menggiatkan
pertumbuhan bibit, tetapi jika konsentrasinya semakin
tinggi justru akan menghambat pertumbuhan bibit.
85
Kecenderungan kontrol dalam menghasilkan nilai
variabel yang tidak lebih baik dibandingkan perlakuan
bahan organik berupa air kelapa muda dengan konsentrasi
25 % diduga disebabkan karena aktivitas kandungan hormon
endogen yang lambat sehingga kurang efektif. Seperti yang
diungkapkan oleh Gardner et al. (1991), seringkali
kandungan zat pengatur tumbuh endogen itu berada di bawah
titik optimal. Dengan demikian dibutuhkan sumber dari
luar untuk menghasilkan respon yang dikehendaki.
Nilai variabel pertumbuhan bibit tebu yang dihasilkan
oleh perlakuan ekstrak kecambah kacang hijau baik pada
konsentrasi 25, 50, ataupun 75 % seluruhnya tidak berbeda
nyata dengan kontrol. Hal ini diduga dapat terjadi akibat
kandungan dari ekstrak kecambah kacang hijau yang lebih
didominasi oleh auksin dan sedikit giberelin. Menurut
Soeprapto (1992), kecambah kacang hijau mengandung asam
amino triptofan. Triptofan merupakan bahan baku sintesis
IAA (Rismunandar, 1992). Menurut Salisbury dan Ross
(1995), giberelin yang terdapat pada ekstrak kecambah
kacang hijau telah berkurang kandungannya seiring dengan
penggunaan cadangannya (giberelin yang terikat dengan
glukosa) dalam proses pengaktifan enzim amilase. Proses
pengaktifan enzim amilase ini berkaitan dengan proses
perkecambahan biji kacang hijau. Selain itu, adanya
endapan tepung halus sebagai hasil sampingan dari
ekstraksi kecambah kacang hijau juga dapat mengganggu
86
proses metabolisme tanaman yang berlangsung di daun
karena bahan organik diaplikasikan melalui daun tebu.
Menurut Djamhari (2010), zat pengatur tumbuh eksogen
yang diaplikasikan pada tanaman berfungsi untuk memacu
pembentukan fitohormon. Hormon dapat mendorong suatu
aktivitas biokimia. Fitohormon sebagai senyawa organik
yang bekerja aktif dalam jumlah sedikit biasanya
ditransformasikan ke seluruh bagian tanaman sehingga
dapat memengaruhi pertumbuhan atau proses-proses
fisiologi tanaman. Hal ini didukung oleh pendapat
Anwaruddin et al. (1996) yang menyatakan bahwa penggunaan
hormon tumbuh eksogen hanya dapat berpengaruh terhadap
fisiologi tanaman jika kandungan hormon di dalam jaringan
tanaman belum mencukupi sehingga menjadi faktor pembatas.
87
V. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Perlakuan air kelapa muda 25 % mampu meningkatkan
tinggi tunas, jumlah daun, diameter tunas, bobot segar
akar, bobot segar tajuk, bobot segar total, bobot
kering akar, bobot kering tajuk, bobot kering total,
volume akar, dan luas daun bibit tebu jika dibandingkan
dengan kontrol (tanpa bahan organik).
2. Perlakuan urin sapi perah 50 %, urin sapi perah 75 %,
ekstrak kecambah kacang hijau 25 %, ekstrak kecambah
kacang hijau 50 %, dan ekstrak kecambah kacang hijau 75
% memberikan hasil yang tidak berbeda nyata dengan
perlakuan tanpa bahan organik pada semua variabel
pertumbuhan bibit bibit tebu.
3. Konsentrasi air kelapa muda yang optimum bagi
pertumbuhan bibit bibit tebu adalah sekitar 39,80 % dan
konsentrasi urin sapi perah yang optimum bagi
pertumbuhan bibit bibit tebu adalah sekitar 34,44 %.
B. Saran
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai
interval pemberian bahan organik sebagai sumber zat
pengatur tumbuh alami yang efektif bagi pertumbuhan
bibit tebu.
88
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai
kandungan zat pengatur tumbuh alami yang terdapat dalam
bahan organik.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai
pengaruh macam dan konsentrasi bahan organik sebagai
sumber zat pengatur tumbuh alami pada umur tebu yang
lebih lama.
89
DAFTAR PUSTAKA
Abdian dan Murniati. 2007. Pemanfaatan urin sapi pada setekbatang tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.). JurnalSains dan Teknologi 6: 1-8.
Abidin, Z. 1985. Dasar–Dasar Pengetahuan tentang ZatPengatur Tumbuh. Angkasa Raya, Bandung.
Ahira, A. 2009. Berkenalan dengan Tanaman Tebu.<http://www.anneahira.com/tanaman-tebu.htm>. Diaksespada tanggal 22 November 2012.
Amilah, Astuti Y. 2006. Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Taogedan Kacang Hijau pada Media Vacin dan Went (VW)terhadap Pertumbuhan Kecambah Anggrek Bulan(Phalaenopsis amabilis L.).<http://www.scribd.com/doc/25831070/PengaruhKonsentrasiEkstrak-Taoge>. Diakses pada tanggal 6April 2013.
Anonim. 2002. Aplikasi Unit Percontohan Agribisnis Terpadudi Lahan Pasirpinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. DinasPertanian Tanaman Pangan Propinsi DIY dengan FakultasPertanian UGM, Yogyakarta.
Anonim. 2005. Bercocok Tanam di Lahan Berpasir.<http://eprints.uny.ac.id/8190/2/bab%201%20-%2005308141009.pdf>. Diakses pada tanggal 2 April2013.
Anonim. 2008. Konsep Peningkatan Rendeman Tebu untukMendukung Proses Akselerasi Industri Gula Nasional.<http://p3gi.net/images/opini/Konsep%20Peningkatan%Rendemen.pdf>. Diakses tanggal 2 Oktober 2012.
Anwaruddin, M. J., N. L. P. Indrayani, S. Hardianti, dan E.Mansyah. 1996. Pengaruh konsentrasi asam giberelat dan
90
lama perendaman terhadap perkecambahan dan pertumbuhanbiji manggis. Jurnal Hortikultura 6: 1-5.
Arifin, B. 2008. Ekonomi Swasembada Gula Indonesia.Economic Review.
Astawan, M. 2005. Kacang Hijau, Antioksidan yang MembantuKesuburan Pria.<http://web.ipb.ac.id/~tpg/de/pubde_ntrtnhlth_kacanghijau.php>. Diakses pada tanggal 6 April 2013.
BMKG. 2013. Data Meteorologi Harian dari PengamatanSinoptik di Stasiun Geofisika Yogyakarta. BadanMeteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Yogyakarta.
Buckman, H. O. dan N. Brasy. 1982. Ilmu Tanah. Bharatakarya Aksara, Jakarta.
Danarto. 2008. Urin Sapi, Potensi yang Terbuang. ArtikelMajalah TROBOS edisi Oktober. PT Permata WacanaLestari, Jakarta.
Darmawijaya, M. I. 1980. Klasifikasi Tanah. BalaiPenelitian Teh dan Kina, Gambung.
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. 2012.<http://www.diperta.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/informasi/artikel/detailartikel/245>. Diakses padatanggal 3 April 2013.
Djamal, A. 2012. Pembuatan Produk Hormon Tumbuhan Komersialdan Pemanfaatan Hormon untuk Berbagai Tujuan.<http://www.jasakonsultan.com/pembuatan-product-hormon-tumbuhan-komersial-dan-pemanfaatan-hormon-untuk-berbagai-tujuan>. Diakses pada tanggal 5 April2013.
Djamhari, S. 2010. Memecah dormansi rimpang temulawak(Curcuma xanthorriza R.) menggunakan larutan atonik danstimulasi perakaran dengan aplikasi auksin. JurnalSains dan Teknologi Indonesia 12: 66-70.
91
Dukes, H. H. 1955. The Physiology of Domestic Animal. ComstockPublishing Associates, New York.
Dwidjoseputro, D. 1989. Pengantar Fisiologi Tumbuhan.Gramedia, Jakarta.
Elawad, S. H., L. H. Allen Jr., and G. J. Gascho. 1982.Response of sugarcane to silicate source and rate: I. Growth and yield. II.Leaf freckling and nutrition. Agronomy Journal 74: 481-484.
Fauzi, A., Y. Sugito, dan S. Soekartomo. 2003. Pengaruhkonsentrasi air kelapa dan nomor ruas terhadappertumbuhan stek kopi arabika Robusta (HEVAII). JurnalHabitat 14: 108-114.
Gardner, F. P., R. B. Pearce, dan R. L. Mitchell. 1991.Fisiologi Tanaman Budidaya. UI Press, Jakarta.
George, E. F. dan P. D. Sherington. 1984. Plant Propagation byTissue Culture. Exegetis Limited, England.
Grimwood, B. E. 1975. Coconut Pala Product, Food, and Agriculture.Organization of the United Nation, Roma.
Gunadi, S. 2002. Teknologi pemanfaatan lahan marginalkawasan pesisir. Jurnal Teknologi Lingkungan 3: 232-236.
Hanafiah, K. A. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Harsanto, B. 1997. Pengaruh pemberian hara NPK dan airkelapa dalam memacu pertumbuhan bibit lada perdu (Pipernigrum L.). Skripsi. Jurusan Budidaya Pertanian,Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Hartmann, H. T. and Kester F. D. 1975. Plant PropagationPrinciples and Practice. Eagle Wood Cliffs, New Jersey.
Heddy, Suwasono. 1989. Hormon Tumbuhan. Rajawali, Jakarta.
Hunt, R. 1978. Plant Growth Analysis. Edward Arnold, London.92
Islami, T. dan W. H. Utomo. 1995. Hubungan Tanah, Air, danTanaman. IKIP Semarang Press, Semarang.
James. 2004. Sugarcane Second Edition. Blackwell Publishing Company,England.
Katuuk, J. R. P. 2000. Aplikasi mikropropagasianggrek macan (Grammatohyllum sciptum) denganmenggunakan air kelapa. Jurnal Penelitian IKIP Manado1: 290-298.
Kertonegoro, B. A., Dja’far, Sulakhudin., dan Ai Dariah.2009. Optimalisasi Lahan Pasir Pantai Bugel.<http://tanahdanlingkungan.blogspot.com/2009/05/optimalisasi-lahan-pasir-pantai-bugel.html>. Diakses tanggal14 November 2012.
Kevin B., K. Dean, and E. Riechers. 2007. Recent developmentsin auxin biology and new opportunities for auxinic herbicide research.Pesticide Biochemistry and Physiology 89 : 1-11.
Kikky. 2012. Fungsi Hormon Auksin, Sitokinin, Giberelin,dan Asam Absisat.<http://rumahhujau.wordpress.com/2012/05/08/fungsi-hormone-auksin-sitokinin-giberelin-dan-asam-absisat/>.Diakses pada tanggal 2 April 2013.
Kristina, N. N. dan S. F. Syahid. 2012. Pengaruh air kelapaterhadap multiplikasi tunas in vitro, produksirimpang, dan kandungan xanthorrhizol temulawak dilapangan. Jurnal Littri 18: 125-134.
Kuntohartono, T. 1982. Pedoman Budidaya Tebu Lahan Kering.Lembaga Pendidikan Perkebunan, Yogyakarta.
Kusumo, S. S. 1984. Zat Pengatur Tumbuh Tanaman. PTSoeroengan, Jakarta.
Lakitan, B. 1995. Fisiologi Pertumbuhan dan PerkembanganTanaman. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
93
Leopold, A. L. 1955. Auxins and Plant Growth. University of CaliforniaPress, Barkeley, Los Angeles.
Lukito, A. 2008. Tebu–Sugarcane.<http://arluki.wordpress.com/2008/10/14/tebu-sugarcane/>. Diakses 23 Juli 2013.
Mahanani, Ayu. 2003. Pengaruh Macam Sumber ZPT Alami danFrekuensi Pemberiannya terhadap Pertumbuhan dan HasilKentang (Solanum tuberosum L.) Varietas Granola.
Mandang, J. P. 1993. Peranan air kelapa dalam kulturjaringan tanaman krisan (Chrysanthemum morifolium RAMAT).Disertasi. Program Pascasarjana, Institut PertanianBogor, Bogor.
Murniati dan E. Zuhry. 2002. Peranan giberelin terhadapperkecambahan benih kopi robusta tanpa kulit. JurnalSAGU 1: 1-5.
Murniati, E. Elita, dan F. Silvina. 2007. Aplikasi organtanaman sebagai sumber giberelin untuk mengaktifkantunas dorman batang nenas bagian tengah. Jurnal SAGU1: 6-9.
Nadia. 2012. Tebu.<http://xa.yimg.com/kq/groups/25896088/44199564/name/Tebu.doc>. Diakses pada tanggal 21 November 2012.
P3GI. 2008. Deskripsi Tebu Varietas Kidang Kencana. PusatPenelitian Perkebunan Gula Indonesia, Pasuruan.
Plantamor. 2012. Informasi Spesies Tomat.<http://www.plantamor.com/index.php?plant= 1165>.Diakses pada tanggal 21 November 2012.
Pramudihasan, A. 2012. Peran Hormon (Auksin, Giberelin,Sitokinin, Asam Absisat, Gas Etilen, dan Kalin) padaPertumbuhan.<http://aghnanisme.blogspot.com/2012/08/peran-hormon-
94
auksin-giberlin-sitokinin.html>. Diakses pada tanggal2 April 2013.
Prawoto, A. A. dan G. Suprijadji. 1992. Kandungan hormondalam air seni beberapa jenis ternak. PelitaPerkebunan 7: 79-84.
Putri, Renata S., Junaidi T. Nurhidayati, Wiwit Budi W.2010. Uji ketahanan tanaman tebu hasil persilangan(Saccharum spp. hybrid) pada kondisi lingkungan cekamangaram (NaCl). Tesis. Institut Teknologi SepuluhNopember, Surabaya.
Rajiman. 2012. Pengelolaan Lahan Pasir Pantai.<http://stppyogyakarta.com/wp-content/uploads/2012/08/4-PENGELOLAAN-LAHAN-PASIR-PANTAI-Rajiman.pdf>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2012.
Rineksane, I. A. 2000. Perbanyakan tanaman manggis secarain vitro dengan perlakuan kadar BAP, air kelapa, danarang aktif. Tesis. Jurusan Budidaya Pertanian,Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta.
Rismunandar. 1992. Hormon Tanaman dan Ternak. PenebarSwadaya, Jakarta.
Rogomulyo, R. 1992. Pengaruh IBA pada Setek Tanaman Nilam(Pogostemon cablin Benth). Fakultas Pertanian,Yogyakarta.
Salisbury, Frank B. dan Cleon W. Ross. 1992. FisiologiTumbuhan. Institut Teknologi Bandung, Bandung.
Salisbury, Frank B. dan Cleon W. Ross. 1995. FisiologiTumbuhan, Perkembangan Tumbuhan, dan FisiologiLingkungan. Institut Teknologi Bandung, Bandung.
Sandra, Edhi. 2011. Hormon dan Pertumbuhan Tanaman.<http://eshaflora.blogspot.com/2011/04/hormon-dan-pertumbuhan-tanaman.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Fee
95
d%3A+KulturJaringanEshaFlora+%28Kultur+Jaringan+Esha+Flora%29>. Diakses padatanggal 5 April 2013.
Savitri, S. V. H. 2005. Induksi akar stek batang SambungNyawa (Gynura drocumbens (Lour) Merr.) menggunakan airkelapa. Skripsi. Fakultas Matematika dan IlmuPengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Sauer, T. J., T. C. Daniel, P. A. More, K. P. Coffey, D. J.Nicholas, and C. P. West. 1999. Poultry litter and grazinganimal waste effects on runoff water quality. Journal of EnvironmentalQuality 28: 860-865.
Septiningsih, E. 2007. Peningkatan produktivitas tanahpasir untuk pertumbuhan tanaman kedelai denganinokulasi mikorhiza dan rhizobium. BIOMA 2: 58 – 61.
Shahab, S., N. Ahmed, and N. S. Khan. 2009. Indole acetic acidproduction and enhanced plant growth promotion by indigenous PSBs.African Journal of Agricultural Research 4: 1312-1316.
Siradz, S. A. dan S. Kabirun. 2007. Pengembangan lahanmarginal pesisir pantai dengan bioteknologi masukanrendah. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan 2: 83-92.
Slem. 2010. Hormon Tumbuhan.<http://slemgaul.wordpress.com/2010/12/03/hormon-tumbuhan/>. Diakses pada tanggal 3 April 2013.
Soepardiman. 1996. Bercocok Tanam Tebu. LPP, Yogyakarta.
Soeprapto, H. S. 1992. Bertanam Kacang Hijau. Penebar Swadaya, Jakarta.
Sriyanti, D. H. 2000. Pembibitan Anggrek dalam Botol.Kanisius, Yogyakarta.
Sudiatso, S. 1983. Bertanam Tebu. Departemen Agronomi.Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
96
Supriadji, G. 1985. Air kemih sapi sebagai perangsang setekkopi. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian 7:11-12.
Supriyadi, A. 1992. Rendemen Tebu Liku-Liku Permasalahannya. Kanisius, Jakarta.
Sutardjo, E. R. M. 2002. Budidaya Tanaman Tebu. BumiAksara, Jakarta.
Sutejo, M. M. 1994. Pupuk dan Cara Pemupukan. Rineka Cipta,Jakarta.
Taiganides, E. P. 1978. Animal Waste Management and Waste WaterTreatment. Elsevler Science Publisher B. V., Amsterdam.
Taiz, L. and E. Zeiger. 1998. Plant Physiology. Sinnuer Associates,Massachuset.
Tanner, C. D. 1968. Evapotranspiration of Water from Plant and Soil.Academic Press, New York.
USDA. 2009. Proteins and Nutrients from Other Beneficial Legumes (Beans):Mung Beans, Mature Seeds, Raw.<http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/cgi-bin/list_nut_edit.pl>. Diakses pada tanggal 6 April 2013.
Wattimena, G. A. 1988. Zat Pengatur Tumbuh Tanaman. PAUIPB dan Sumberdaya Informasi IPB, Bogor.
Wattimena, G. A., Dinarti D., Rahayu M. S., and Dahniar N.2003. Preliminary Study on the Effect of Coconut Water and Aspirin onIn Vitro Conservation of Sweet Potato (Ipomoea batatas L.) cv.Sukuh. Organized Jointly by Departement of Agronomy, Faculty ofAgriculture Bogor Agricultural University and International Potato CenterRegional Officer far East Asia and the Pacific (CIP-ESEAP), Bogor.
Widiastoety, D., S. Kusumo, dan Syafni. 1997. Pengaruhtingkat ketuaan air kelapa dan jenis kelapa terhadappertumbuhan plantet anggrek Dendrobium. JurnalHortikultura 7: 768-772.
97
Widyastuti, N. dan D. Tjokrokusumo. 2007. Peranan beberapazat pengatur tumbuh tanaman pada kultur in vitro.Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia 3: 55-63.
Wilkins, Malmcom B. 1989. Fisiologi Tanaman. Bina Aksara,
Jakarta.
William, D., A. Teale, I. Paponov, and K. Palme. 2006. Auxinin action: signalling, transport and the control of plant growth anddevelopment. Journal of Molecular Cell Biology 7: 847-859.
Yong, J. W. H., Ge L., dan Y. F. Ng. 2009. The ChemicalComposition and Biological Properties of Coconut (Cocos nucifera L.)Water. Natural Sciences and Science Education Academic Group,Nanyang Technological University, I Nanyang Walk, Singapore.
Yuwono, N. W. 2009. Membangun kesuburan tanah di lahanmarginal. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan 2: 137-141.
Zamroni dan Darini. 2009. Pengaruh Zat Pengatur TumbuhAlami dan Defoliasi Daun pada Pertumbuhan Setek CabeJamu. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa,Yogyakarta.
Zhao, Y. 2010. Auxin biosynthesis and its role in plant development. Annu.Rev. Plant Biol. 61: 49-64.
98