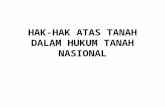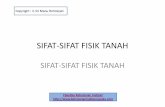Sholeh Avivi. PENGARUH LAMA STERILISASI MEDIA TUMBUH DAN VARIASI LENGAS TANAH DALAM MENEKAN...
Transcript of Sholeh Avivi. PENGARUH LAMA STERILISASI MEDIA TUMBUH DAN VARIASI LENGAS TANAH DALAM MENEKAN...
1
PENGARUH LAMA STERILISASI MEDIA TUMBUH DAN VARIASI LENGAS TANAH
DALAM MENEKAN PERKEMBANGAN Aspergillus flavus PADA KACANG TANAH
Sholeh Avivi
Jurusan Budidaya Pertanian., Fakultas Pertanian Universitas Jember,
Jl. Kalimantan 37, Jember 68121, e-mail: [email protected]
ABSTRACT
Avivi, S. 2005. Effect of Soil Sterility and Soil Water Content Treatments in Reducing the
Aspergillus flavus Development on Peanut. Agrikultura 16(3): 189-194.
The peanut seed that were infected by A. flavus could contain aflatoxin, the heart
cancer cause. The A. flavus contamination could be reduced by agronomic treatment. The
aims of this research were: (1) to reduce the A. flavus infection on peanut seed and pod by
agronomic treatment, (2) to investigate the effect of soil steril and soil water content
treatments on A. flavus infection, and (3) to find the best agronomic technique to control the
A. flavus. Complete randomized design factorial with five replication and two factors was
used to achieve those objectives. The result showed that the interaction between soil steril
and soil water content treatments was not significant. The soil water content 70%-80% field
capacity (FC) significantly affect total pod weight, spores number on pod, spores density on
pod, and A. flavus infection on pod. Soil sterilization using hot water steam 10 hours
significantly affected the total plant weight and the number of abnormal pod. The best
treatment to reduce the infection of A. flavus on peanut plantation was soil water content
70%-80% field capacity. This treatment could reduce A. flavus infection on pod until 500%
compare to the 100% FC treatment.
Key words: A. flavus, soil water content, soil sterility, peanut
ABSTRAK
Biji kacang tanah yang terinfeksi A. flavus mengandung aflatoksin, zat beracun
penyebab kanker hati. Serangan A. flavus dapat dikurangi dengan beberapa perlakuan dalam
praktek budidaya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengurangi infeksi A. flavus pada biji
atau polong kacang tanah selama proses budidaya (2) mengetahui pengaruh sterilisasi tanah
dan lengas tanah terhadap perkembangan A. flavus (3) menemukan teknik budidaya terbaik
untuk mengontrol A. flavus selama budidaya kacang tanah. Penelitian dilaksanakan
2
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial 5 ulangan dengan dua faktor, yaitu
lengas tanah dan sterilisasi tanah dengan uap air panas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tidak ada interaksi antara perlakuan lengas tanah dan sterilisasi tanah pada semua parameter.
Lengas tanah 70%-80% kapasitas lapang (KL) berpengaruh nyata pada parameter berat
polong total per polybag, diameter A. flavus pada polong, persentase polong terserang A.
flavus, dan jumlah spora A. flavus pada polong. Sterilisasi tanah selama 10 jam berpengaruh
nyata pada berat berangkasan kering total per polybag dan jumlah polong hampa per polybag.
Perlakuan terbaik untuk mengurangi perkembangan A. flavus selama proses budidaya kacang
tanah adalah lengas tanah 70%-80% KL. Perlakuan ini dapat menurunkan serangan A. flavus
pada polong hingga 500% dibandingkan dengan perlakuan lengas tanah 100% KL.
Kata kunci: A. flavus, lengas tanah, sterilisasi tanah, kacang tanah
PENDAHULUAN
Kondisi iklim tropis Indonesia yang berkelembaban tinggi dan cara budidaya serta
cara penanganan pasca panen kacang tanah yang selama ini dipraktekkan, sangat
mempengaruhi perkembangan dan penyebaran A. flavus, fungi yang menghasilkan aflatoxin.
Aflatoxin adalah mikotoksin yang terbentuk saat kacang tanah terinfeksi oleh fungi A. flavus
dan atau A. parasiticus. Toksin ini menyebabkan hepatotoksik, karsinotoksik, dan
teratogenik (Duryatmo, 2001a; b). Sebanyak 58% kejadian kanker liver dan tumor liver
(hepatitis carcinoma) telah dideteksi disebabkan oleh aflatoksin (Bryden 1999; Sudjadi et. al.
1999; Rais, 1998).
Selama ini kandungan aflatoxin pada kacang tanah impor maupun lokal kurang
diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, masih banyak biji
kacang tanah yang terasa pahit jika dikonsumsi dan ini menunjukkan kandungan aflatoxinnya
lebih dari 1000 ppm. Penyebabnya adalah infeksi A. flavus pada pertanaman kacang tanah di
lapang, pada benih kacang tanah di penyimpanan, benih di pasaran, dan pada biji konsumsi,
kerusakannya mencapai 60-80% dengan kandungan aflatoksin 40-4100 ppm. Sedangkan
kandungan aflatoksin pada kacang tanah siap saji yang beredar di supermarket dan pasar-
pasar lokal mencapai 1000 ppm (Sudjadi et. al. 1999).
Banyak negara menetapkan syarat standar kualitas yang ketat bagi kacang tanah. India
sebagai salah satu produsen kacang tanah terbesar menetapkan 30 ppm aflatoksin setiap
kilogram kacang tanah, Badan Kacang Tanah Afrika menetapkan 400 ppm, Masyarakat
Ekonomi Eropa (MEE) 40 ppm, Amerika Serikat 20 ppm, dan Australia 15 ppm. Syarat
tersebut lebih rendah dari ketentuan FAO dan WHO yang menetapkan kadar aflatoksin
3
maksimum 50 ppm (Duryatmo, 2001b; Hansen & Norman 1999). Di Indonesia sejauh ini
belum ada ketentuan resmi dari pemerintah
Kontaminasi aflatoxin pada kacang tanah telah menjadi masalah di seluruh
pertanaman kacang tanah dunia (Will et al. 1994). Penggenangan lahan telah diketahui dapat
menurunkan resiko dan tingkat kontaminasi aflatoxin (Hansen & Norman 1999). Menurut
Schearer et al. (1999) produksi aflatoxin pada biji kacang tanah terjadi apabila kacang tanah
terinfeksi oleh fungi A. flavus dan atau A. parasiticus. Kedua fungi tersebut hanya dapat
berkembang pada kondisi lengas tanah 80-95% dan temperatur 25-320C. Pada kisaran lengas
tanah dan suhu di luar kondisi tersebut kedua fungi tersebut hampir tidak dapat berkembang.
Infeksi A. flavus dan A. parasiticus di lapang dapat berasal dari fungi yang sudah
berkembang di lahan pertanian, karena itu rotasi tanaman dapat digunakan untuk mengurangi
infeksi fungi tersebut (Wright & Cruickshank 1999). Kondisi tanah yang telah steril dengan
perlakuan tertentu dapat dipastikan akan mengurangi infeksi.
Kontaminasi Aspergillus dapat dikurangi dengan memberi perlakuan budidaya dan
perlakuan pascapanen hingga di penyimpanan yaitu perlakuan kandungan air media tanam,
rotasi tanaman, pengaturan kepadatan tanaman, pengaturan iklim mikro tanah dengan
pemberian mulsa, penggunaan varietas tahan kering di lahan kering, cara dan intensitas
pengeringan saat panen, teknik pencucian dan penggunaan fungisida sebelum benih disimpan,
dan sebagainya (Piva et al., 1995; Schearer et al 1999; Wright & Cruicksank 1999).
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengurangi infeksi A. flavus pada biji atau polong
kacang tanah selama proses budidaya (2) mengetahui pengaruh sterilisasi tanah dan lengas
tanah terhadap perkembangan A. flavus (3) menemukan teknik budidaya terbaik untuk
mengontrol A. flavus selama budidaya kacang tanah.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di rumah kaca jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian
Universitas Jember pada bulan April sampai dengan bulan Oktober 2002.
1. Uji polong dan biji kacang tanah terinfeksi A. flavus di laboratorium. Benih kacang
tanah disortir lebih dahulu, kemudian benih yang disortir dan tidak disortir diuji untuk
mengetahui tingkat serangan A. flavus pada polong dan biji. Uji dilakukan dengan Uji Kertas
Digulung Dalam Plastik (UKDDP). Sebanyak 15 polong dan 25 biji kacang tanah disterilisasi
dengan NaClO 1,25% selama 10 menit, dibilas dengan H2O steril. Polong atau biji ditata
pada 5 lembar kertas merang basah steril, digulung dan diinkubasikan pada alat pengecambah
benih (3 kali ulangan). Setelah 3 hari inkubasi, dihitung jumlah polong atau biji yang
terinfeksi A. flavus. Fungi diidentifikasi secara mikroskopis. Serangan fungi yang bukan A.
flavus tidak diamati dalam penelitian ini.
4
2. Uji persentase biji terinfeksi A. flavus dari tanaman yang ditumbuhkan pada tanah
yang disterilkan dengan lama bervariasi dan lengas tanah yang berbeda. Uji ini
dilakukan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan dua faktor yaitu
(1) lama sterilisasi media tanam dengan 3 taraf yaitu: media dipanaskan dengan uap air panas
pada suhu 80-900C 5 jam (S2), 10 jam (S3). Sedangkan kontrolnya digunakan media yang
tidak dipanaskan (S1); (2) lengas tanah dengan 3 taraf yaitu: A1 lengas tanah 100% KL, A2
lengas tanah 85%-95% KL, dan A3 lengas tanah 70%-80% KL. Dengan demikian terdapat 9
kombinasi perlakuan. Setiap perlakuan diulang 5 kali.
Media tumbuh yang digunakan adalah campuran tanah top soil, pasir, dan pupuk
kandang (1:1:1 v/v). Tiap polibag berisi 8 kg media steril dan ditanami dengan 2 biji kacang
tanah yang sudah disterilisasi permukaannya. Penjarangan dilakukan pada 7 hari setelah
tanam (7 HST) dengan menyisakan 1 tanaman per polibag. Selama pertumbuhan tanaman,
lengas tanah dijaga dengan mengatur lengas tanah sesuai perlakuan. Pada saat panen yaitu
pada 90 HST diamati (1) berat berangkasan total per polybag, (2) berat polong total per
polybag, (3) jumlah polong normal per polybag, dihitung berdasarkan kriteria fisik (warna
dan bentuk), (4) persentase polong terserang A. flavus, dihitung dengan metode UKDDP, di-
shaker dalam aquades, dan menggunakan media agar selama10 hari, (5) jumlah biji normal
per polybag, dihitung berdasarkan kriteria fisik (warna dan bentuk), (6) berat 100 biji per
perlakuan, (7) persentase biji yang terserang A. flavus, dihitung dengan metode UKDDP, di-
shaker dalam aquades, dan menggunakan media agar selama 10 hari, dan (8) daya
berkecambah, dihitung dengan metode UKDDP.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah polong dan biji kacang tanah terinfeksi A. flavus sebelum tanam. Penyortiran
polong kacang tanah normal sebelum tanam dilakukan berdasarkan karakteristik umum
polong normal antara lain: polong berbentuk utuh dengan guratan yang jelas, tidak tampak
kusut, kulit polong berwarna coklat normal dan keras, sedangkan untuk benih dipilih yang
sehat berwarna merah muda dengan bentuk utuh, tidak kusut dan bernas. Penyortiran polong
dan benih sebelum tanam sangat efektif mengurangi serangan A. flavus pada polong dan
benih sampai dengan 50%. (Tabel 1).
Tabel 1. Persentase infeksi A. flavus pada polong dan benih
Perlakuan % polong terinfeksi % benih terinfeksi
Tidak Disortir 41a 44a
Disortir 26a 22b
Rerata dari lima kali ulangan yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan berbeda tidak nyata berdasar uji Duncan pada taraf 5%.
5
Uji persentase biji terinfeksi A. flavus dari tanaman yang ditumbuhkan pada tanah
steril dengan lengas tanah yang berbeda
Pada percobaan ini, hasil perhitungan pada semua parameter menunjukkan tidak
terdapat interaksi antara faktor sterilisasi media tanam dengan faktor lengas air tanah.
Interaksi antara kedua faktor perlakuan menunjukkan berbeda tidak nyata pada taraf 5%
(Tabel 2 dan Tabel 3).
Pada minggu pertama setelah tanam sampai minggu keempat setelah tanam lengas
tanah mempengaruhi tinggi tanaman. Tanaman-tanaman dengan perlakuan lengas tanah 100%
KL lebih cepat mencapai tinggi maksimal daripada tanaman-tanaman dengan lengas tanah
lebih rendah (data pengamatan mingguan tidak ditunjukkan). Makin tinggi kandungan air
media memungkinkan ketersediaan hara yang lebih baik, sehingga memungkinkan tanaman
menyerap hara lebih baik.
Menurut Fitter dan Hay (1991), laju pertumbuhan sel-sel tanaman dan efisiensi proses
fisiologis mencapai tingkat tertinggi bila sel-sel berada pada turgor maksimum yang dapat
dicapai jika kandungan air tanah optimum. Sedangkan Jumin (1992) menyatakan bahwa
lengas tanah yang lebih tinggi menyebabkan penampakan dinding sel menjadi lebih lunak dan
sel-sel tanaman lebih mudah mengalami pemanjangan. Cekaman air yang lama dapat
meningkatkan tebal dan kepadatan kutikula, menurunkan pemasukan, pelaluan air, dan
metabolisme dalam tubuh tanaman. Status ini menimbulkan kelambatan pada pertumbuhan
batang dan daun, mengurangi pembelahan sel dan mengurangi sintesa protein.
Sterilisasi media tanam dan lengas tanah mempunyai pengaruh tidak nyata pada
jumlah polong total per polybag, polong normal per polybag, dan berat 100 biji per perlakuan,
namun sterilisasi media tanam berpengaruh nyata pada jumlah polong hampa per polybag.
Sterilisasi media tanam yang tinggi menyebabkan lebih banyak hara yang teroksidasi.
Ketersediaan hara yang rendah, terutama hara makro, mengakibatkan pengisian polong
menjadi berkurang, sehingga tanaman-tanaman dengan perlakuan sterilisasi media tanam
lebih tinggi mempunyai polong hampa yang tinggi pula. Fitter dan Hay (1991) menyebutkan
bahwa pertumbuhan yang optimum dari suatu tanaman membutuhkan suplai yang cukup
untuk semua hara, sehingga terjadi interaksi yang nyata
Sementara itu, saat pembentukan polong lengas tanah mempunyai pengaruh yang
lebih besar dibandingkan dengan sterilisasi media tanam. Taraf perlakuan lengas tanah 85%-
95% KL (A2) menghasilkan polong total lebih banyak dibandingkan dengan lengas tanah
100% KL (A1) dan lengas tanah 70%-80% KL (A3). Kacang tanah dengan lengas tanah 100%
KL (A1) dapat mencapai tinggi tanaman maksimal, namun dengan tinggi maksimal ginofor
yang terbentuk banyak yang tidak dapat mencapai permukaan tanah. Oleh karena itu polong
yang terbentuk relatif lebih sedikit daripada lengas tanah 85%-95% KL (Tabel 3).
6
Tabel 2. Rerata hasil pengamatan akibat pengaruh sterilisasi media tanam
No Parameter Lama Sterilisasi Media
0 jam 5 jam 10 jam
1. Berat 100 benih/perlakuan (gram) 39,6 41,7 39,0
2. Berat polong total/perlakuan (gram) 45,7 51,9 50,5
3. Berat basah brangkasan (gram) 82,1 93,3 98,2
4. Berat kering brangkasan (gram) 60,9a 79,0ab 70,4b
5. Tinggi tanaman (cm) 47,2 48,0 48,7
6. Jumlah polong total perpolibag 17,1 21,5 22,1
7. Jumlah polong normal perpolibag (butir) 14,7 17,9 17,0
8. Jumlah polong hampa (butir) 2,5a 3,7a 5,1b
9. Jumlah spora A. flavus pada polong 0,9 0,7 0,8
10. Jumlah spora A. flavus pada benih 0,4 0,1 0,2
11. Persentase polong terserang A. flavus 29,6 14,8 22,2
12. Persentase polong terserang A. flavus 1,1 0,4 0,7
13. Daya Kecambah 97,8 94,4 95,6
Keterangan: angka rata-rata dari lima kali ulangan yang diikuti huruf yang sama pada baris
yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata berdasar uji Duncan pada taraf 5%.
Tabel 3. Rerata hasil pengamatan akibat pengaruh variasi lengas tanah
No Parameter Lengas tanah
100% KL 85-95% KL 70-80% KL
1. Berat 100 benih/perlakuan (gram) 40,6 40,0 39,7
2. Berat polong total/perlakuan (gram) 54,8a 52,3a 41,0b
3. Berat basah brangkasan (gram) 95,6 90,7 87,3
4. Berat kering brangkasan (gram) 74,6 70,7 64,8
5. Tinggi tanaman (cm) 47,1 50,1 46,8
6. Jumlah polong total perpolibag 21,2 22,1 17,4
7. Jumlah polong normal perpolibag (butir) 17,0 17,9 14,6
8. Jumlah polong hampa (butir) 4,2 4,2 2,8
9. Jumlah spora A. flavus pada polong 1,4a 0,7b 0,2c
10. Jumlah spora A. flavus pada benih 0,4 0,4 0,0
11. Persentase polong terserang A. flavus 40,7a 18,5b 7,4c
12. Persentase polong terserang A. flavus 1,1 1,1 0,0
13. DK=Daya Kecambah 93,3 96,7 97,8
Keterangan: angka rata-rata dari lima kali ulangan yang diikuti huruf yang sama pada baris
yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata berdasar uji Duncan pada taraf 5%.
Tanaman kacang tanah dengan lengas tanah 85%-95% KL dapat menghasilkan polong
terbanyak. Lengas tanah 85%-95% KL menghasilkan tinggi tanaman yang optimum untuk
pembentukan ginophor. Ginofor yang terbentuk dapat lebih mudah mencapai permukaan
tanah, sehingga lebih banyak polong yang terbentuk.
Lengas tanah 70%-80% KL menghasilkan polong yang paling sedikit (Tabel 3).
Lengas tanah yang rendah akan menyebabkan cekaman air, menghambat pembentukan dan
pengisian polong. Masa reproduktif tanaman menjadi lebih singkat. Jumin (1992)
7
mengungkapkan bahwa pembungaan, pembuahan, dan pengisian biji/buah akan gagal bila
cekaman air berlangsung lama.
Berkurangnya polong yang terbentuk pada perlakuan lengas tanah 70%-80% KL (A3)
juga dapat diakibatkan menurunnya aktifitas fotosintesis yang diakibatkan oleh kurangnya air.
Kekurangan air menyebabkan pengambilan hara dari tanah berkurang dan stomata pada daun
menutup, sehingga hasil akhir berkurang. Menurut Fitter dan Hay (1991), bahwa cekaman air
ringan sampai sedang menyebabkan penutupan stomata, sehingga memotong suplai karbon
dioksida ke sel-sel mesofil. Sementara Noggle dan Fritz (1983) menyampaikan bahwa hasil
akhir fotosintesis dan translokasinya dari daun menurun seiring dengan menurunnya kapasitas
air. Menurunnya aktifitas fotosintesis serta berkurangnya translokasi hasil fotosintesis dari
daun akan menghambat proses-proses metabolisme lain dalam tanaman, termasuk
pembentukan bunga dan polong.
Lama sterilisasi media tanam juga mempunyai pengaruh yang lebih beragam terhadap
berat 100 biji per perlakuan daripada lengas tanah (Tabel 3), walaupun berbeda tidak nyata.
Sterilisasi dengan lengas tanah lebih tinggi mempunyai kadar berat 100 biji per perlakuan
lebih kecil. Kadar hara yang lebih rendah menyebabkan saat pengisian polong menjadi kurang
maksimal. Hasil metabolisme dalam bentuk protein dan karbohidrat yang banyak
terakumulasi dalam biji menjadi lebih rendah, sehingga berat akhir biji juga lebih rendah.
Perkembangan A. flavus sangat dipengaruhi oleh lengas air tanah. Lengas tanah yang
tinggi menyebabkan kelembaban media juga lebih tinggi. Kelembaban yang tinggi sangat
baik bagi perkembangan fungi termasuk pula fungi A. flavus. Media dengan lengas tanah
100% KL lebih banyak mengandung spora A. flavus (Tabel 3)
Uji serangan fungi dengan substrat kertas saring menunjukkan infeksi A. flavus lebih
banyak terjadi pada polong daripada biji. Perbedaan jumlah polong yang terinfeksi A. flavus
pada hari kelima dan ketujuh menunjukkan media dengan lengas tanah 100% KL mempunyai
persentase polong terserang A. flavus lebih tinggi daripada media dengan lengas tanah 85%-
95% KL dan media dengan lengas tanah 70% - 80% KL. Diameter perkembangan spora lebih
cepat terjadi pada lengas tanah yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan spora lebih banyak
terdapat pada polong dengan lengas tanah yang lebih tinggi.
Kerapatan (jumlah) spora yang menginfeksi polong kacang tanah dengan lengas tanah
100% KL lebih tinggi daripada kacang tanah dengan lengas tanah yang lebih rendah,
demikian pula dengan biji kacang tanah, bahkan pada lengas tanah 70%- 80% KL tidak
ditemukan adanya spora A. flavus pada biji kacang tanah (Tabel 3).
Perkembangan A. flavus, baik pada biji ataupun polong dipengaruhi oleh menurunnya
lengas air tanah. Lengas tanah yang rendah menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan
fungi ini terhambat. Lengas tanah yang rendah juga akan menurunkan kelembaban tanah.
Kelembaban yang rendah akan mengurangi penyebaran spora dan hifa fungi. Pada penelitian
8
ini persentase polong yang terserang A. flavus pada perlakuan lengas tanah paling rendah (70-
80% KL) dapat menurunkan serangan hingga 500% jika dibandingkan dengan perlakuan
lengas tanah 100% KL. Fakta ini sejalan dengan pendapat Rahmianna (2001) dalam
Duryatmo (2001a) yang menyebutkan bahwa A. flavus dan A. parasiticus hanya dapat
berkembang baik pada kisaran lengas tanah 80%-95%. Alexopoulus dan Mims (1994) juga
menyebutkan bahwa populasi A. flavus akan menurun selama musim kering. Dengan
demikian mungkin akan lebih tepat jika penanaman kacang tanah dilakukan pada akhir musim
kering (September sampai November).
SIMPULAN
Tidak terdapat interaksi antara faktor sterilisasi media tanam dan lengas air tanah.
Sterilisasi media tanam berpengaruh nyata pada berat berangkasan kering total per polybag
dan jumlah polong hampa per polybag. Sedangkan lengas tanah berpengaruh nyata pada berat
polong total per polybag dan berpengaruh sangat nyata pada diameter perkembangan A. flavus
pada polong, persentase polong terserang A. flavus, dan jumlah spora A. flavus pada polong.
Perlakuan terbaik untuk mengurangi infeksi A. flavus di pertanaman kacang tanah
adalah lengas tanah 70%-80% (A3). Perlakuan ini dapat menurunkan serangan A. flavus pada
polong hingga 500% dibandingkan dengan perlakuan lengas tanah 100% KL (A1).
UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih disampaikan kepada Proyek DUE Universitas Jember (IBRD Loan No. 4043-
IND) atas bantuan dana penelitian, kepada Heru Purwadi atas bantuan melaksanakan
penelitian, kepada Prof. Dr. Wiwiek Sri Wahyuni, MS dan Ir. Sugeng Winarso, MSi. atas
saran penting untuk perbaikan naskah ini.
9
DAFTAR PUSTAKA
Alexopoulus and Mims. 1979. Introductory Mycology. 3rd
Edition. John Willey and Sons's.
New York.
Bryden, WL. 1999. Aflatoxin and Reduction in Contaminated Commodities. Pp. 18-20 in
ACIAR proceeding: Elimination of Aflatoxin Contamination in Peanuts. (RG.
Dietzgen ed). Pirie Printers Pty Limited, Canberra.
Duryatmo, S. 2001a. Racun Mematikan Itu Bernama Aflatoxin. Trubus 374. Januari
2001/XXXII. pp 69-70.
__________. 2001b. Maaf Semua Pintu Tertutup bagi Aflatoxin, Trubus 374. Januari
2001/XXXII pp 70.
Fitter, AH and RKM. Hay. 1994. Fisiologi Lingkungan Tanaman. (Terjemahan). Gadjah
Mada University Pers. Yogyakarta.
Hansen, RB and KL. Norman. 1999. Economic Importance of Aflatoksin to The Australian
Peanuts Industry. Pp. 7–9 in ACIAR Proceeding Elimination of Aflatoxin
Contamination in Peanuts. (RG. Dietzgen ed.). Pirie Printers Pty Limited, Canberra.
Noggle, GR and GJ Fritz. 1983. Introductory Plant Physiology. Prentice Hall. New Jersey.
Jumin, HB. 1992. Ekologi Tanaman Suatu Pendekatan Fisiologis. Rajawali Pers. Jakarta.
Piva, GF, Galvano, A Pietri, and A Piva. 1995. Detoxification methods of Alatoxin: A
Review. New York. Agricola 1997.
Rais, SA. 1998. Groundnut Breeding in Indonesia. Contribution Paper in ACIAR Project
Annual Meeting, Bogor. 10p.
Schearer, C, GC Wright, S Krosch, J Tatnell, and A Kyei. 1999. Effect of Temperature on
Growth and Aflatoxin Production by Non Toxigenic and Toxigenic Aspergillus flavus.
ACIAR Food Legumes Newsletter. 28:(in press).
Sudjadi, S, M Mahmud, DS Damardjati, A Hidayat, and A Widiawati. 1999. Aflatoxin
Research in Indonesia. Pp. 23–25 in ACIAR Proceeding: Elimination of Aflatoxin
Contamination in Peanut. (RG. Dietzgen ed). Pirie Printers Pty Limited, Canberra.
Will, ME, CC Holbrook, and DM Wilson. 1994. Evaluation of field inoculation techniques
for screening peanut genotypes for reaction to preharvest A. flavus group infection and
aflatoxin contamination. Peanut Science. 21:122-125.
Wright, GC and AL Cruickshank. 1999. Agronomic, genetic, and crop modelling strategies
to minimise aflatoxin contamination in peanut. Pp. 12-17 in ACIAR Proceeding:
Elimination of Aflatoxin Contamination in Peanut. (RG. Dietzgen ed.). Pirie Printers
Pty Limited, Canberra.