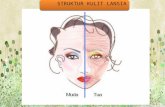pengaruh gel ekstrak kulit buah delima - Universitas Brawijaya
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of pengaruh gel ekstrak kulit buah delima - Universitas Brawijaya
i
PENGARUH GEL EKSTRAK KULIT BUAH DELIMA
(Punica granatum L.) TERHADAP JUMLAH SEL LIMFOSIT PADA
PROSES PENYEMBUHAN ULKUS TRAUMATIK TIKUS PUTIH (Rattus
norvegicus) YANG DIINDUKSI PANAS
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran Gigi
Oleh :
Audry Theavasthy
NIM. 145070401111036
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018
ii
LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
PENGARUH GEL EKSTRAK KULIT BUAH DELIMA (Punica granatum L.)
TERHADAP JUMLAH SEL LIMFOSIT PADA PROSES PENYEMBUHAN ULKUS
TRAUMATIK TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) YANG DIINDUKSI PANAS
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran Gigi
Telah diuji pada
Hari : Rabu
Tanggal : 14 Maret 2018
Telah dinyatakan lulus oleh:
Penguji I
drg. Miftakhul Cahyati, Sp.PM
NIP. 197708032010122001
Penguji II/Pembimbing I Penguji III/Pembimbing II
drg. Nenny Prasetyaningrum, M.Ked drg. Robinson Pasaribu, Sp. BM NIK. 2009028129222001 NIP. 197304052000121007
Mengetahui,
Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya
drg. R. Setyohadi, MS
NIP. 195802121985031003
iii
IDENTITAS TIM PENGUJI
1. Penguji I
Nama : drg. Miftakhul Cahyati, Sp.PM
NIP/NIK : 197708032010122001
Status : Dosen PNS
Pangkat : Penata Muda Tk.I
Golongan : III/b
Jabatan Akhir : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : Sp 1
Agama : Islam
Alamat : Sidomakmur No. 52, Kepanjen Malang
2. Penguji II
Nama : drg. Nenny Prasetyaningrum, M.Ked
NIP/NIK : 2009028129222001
Status : Dosen Tetap Non PNS
Pangkat : Penata Muda Tk.I
Golongan : III/b
Pendidikan Terakhir : S2
Agama : Islam
Alamat : Jl. K.H Hasyim Ashari 5c Malang/
Jl, Welirang 10 Malang
3. Penguji III
Nama : drg. Robinson Pasaribu, Sp.BM
NIP/NIK : 197304052000121007
Status : Dosen Luar Biasa
Pangkat : Penata Tk.I
Golongan : III/d
Pendidikan Terakhir : Sp 1
Agama : Kristen
Alamat : Jl. Gambuta Blok B No. 40, Tidar Malang
iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Audry Theavasthy
NIM : 145070401111036
Program Studi : Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya
menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar
hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain
yang saya akui sebaga tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari
dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah jiplakan, maka saya bersedia
menerima sanksi atas perbuatan tersebut.
Malang, 14 Maret 2018
Yang membuat pernyataan,
Audry Theavasthy
NIM. 145070401111036
v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Audry Theavasthy
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 21 Januari 1997
Status : Belum Menikah
Alamat : Jalan Kertoraharjo No. 67B, Malang
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Nomor HP : 082234457617
Email : [email protected]
Pendidikan Formal :
1. SD 2 Barongan, Dari tahun 2003 - 2008
2. SMP 1 Kudus, Dari tahun 2008 - 2011
3. SMA 1 Kudus, Dari tahun 2011 - 2014
Hormat Saya,
Audry Theavasthy
vi
ABSTRAK
Theavasthy, Audry. 2018. Pengaruh Gel Ekstrak Kulit Buah Delima (Punica granatum L.) Terhadap Jumlah Sel Limfosit Pada Proses Penyembuhan Ulkus Traumatik Tikus Putih (Rattus norvegicus) Yang Diinduksi Panas. Skripsi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Brawijaya. Pembimbing: (I) drg. Nenny Prasetyaningrum, M.Ked (II) drg. Robinson Pasaribu, Sp. BM
Ulkus traumatik merupakan lesi di rongga mulut yang sering dijumpai. Triamcinolone acetonide 0.1% merupakan obat untuk mengobati ulkus, dalam penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kandidiasis oral. Gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) mengandung ellagic acid dan flavonoid yang dapat meningkatkan aktivitas limfosit sehingga mempercepat penyembuhan ulkus. Jenis penelitian ini menggunakan eksperimental Post Test Only Randomized Control Grup Design untuk mengetahui pengaruh gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) terhadap jumlah limfosit pada proses penyembuhan ulkus traumatik tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi panas. Sampel 27 tikus dibagi menjadi 9 kelompok dengan 3 time series, yaitu kelompok tanpa perlakuan (K(-)), kelompok yang diaplikasikan Triamcinolone acetonide 0.1% (K(+)) dan kelompok yang diaplikasikan gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.). Sampel dipilih dengan teknik Simple Random Sampling. Variabel yang diteliti adalah sel limfosit pada mukosa labial tikus putih (Rattus norvegicus) dari sediaan HPA dengan pengecatan HE. Data penelitian dianalisis dengan uji One Way Analysis of Variant (ANOVA), didapatkan hasil perbedaan yang signifikan antar kelompok dengan nilai signifikan sebesar p=0.000 (p<0.05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) berpengaruh terhadap jumlah limfosit pada proses penyembuhan ulkus traumatik tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi panas.
Kata kunci: kulit buah delima (Punica granatum L.), limfosit, ulkus traumatik
vii
ABSTRACT
Theavasthy, Audry. 2018. The Effectivity of Gel Extract Pomegranate Peel (Punica granatum L.) to The Number of Lymphocyte on The Healing Process of Traumatic Ulcer of White Rat (Rattus norvegicus) which Heat Induced. Thesis, Faculty of Dentistry, Brawijaya University. Advisors: (I) drg. Nenny Prasetyaningrum, M.Ked (II) drg. Robinson Pasaribu, Sp. BM
Traumatic ulcers are lesions of the oral cavity that are commonly encountered. Triamcinolone acetonide 0.1% is drug to treat ulcers, but in long-term use may lead to oral candidiasis. Pomegranate peel extract gel (Punica granatum L.) contains ellagic acid and flavonoids that can increase lymphocyte activity so as to accelerate ulcer healing. The research used experimental Post Test Only Randomized Control Group Design to know the effect of pomegranate peel extract gel (Punica granatum L.) to the number of lymphocytes in the healing process of traumatic ulcer of white rat (Rattus norvegicus) which heat induced. The sample of 27 rats was divided into 9 groups with 3 time series, which is the untreated treatment group (K (-)), the group was applied Triamcinolone acetonide 0.1% (K (+)) and the group was applied pomegranate peel extract gel (Punica granatum L. ). The sample were selected using Simple Random Sampling technique. The variables studied were lymphocyte cells in labial mucosa of white rat (Rattus norvegicus) from HPA preparation with HE staining. Research data was analyzed by One Way Analysis of Variant (ANOVA) test, there were significant differences between groups with significant value of p = 0.000 (p <0.05). The conclusions of this study are pomegranate peel extract gel (Punica granatum L.) takes effect on the number of lymphocytes in the healing process of traumatic ulcer in white rat (Rattus norvegicus) which induced heat.
Keyword: pomegranate peel (Punica granatum L.), lymphocyte, traumatic ulcers
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah, dan
inayah-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan
skripsi yang berjudul “Pengaruh Gel Ekstrak Kulit Buah Delima (Punica granatum
L.) Terhadap Jumlah Sel Limfosit Pada Proses Penyembuhan Ulkus Traumatik
Tikus Putih (Rattus norvegicus) Yang Diinduksi Panas”.
Begitu banyak dukungan dan perhatian yang penulis dapatkan selama
penyusunan skripsi ini sehingga hambatan dan kesukaran dapat dilalui. Oleh
karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih dan
penghargaan sebesar-besarnya kepada:
1. drg. Setyohadi, M.S selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas
Brawijaya Malang.
2. drg. Kartika Andari Wulan Sp. Pros selaku Ketua Program Studi Sarjana
Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya.
3. drg. Nenny Prasetyaningrum, M.Ked sebagai pembimbing pertama yang
telah memberikan bimbingan, masukan, dan semangat sehingga penulis
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. drg. Robinson Pasaribu, Sp.BM sebagai pembimbing kedua yang telah
memberikan bimbingan, masukan, dan semangat sehingga penulis dapat
menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. drg. Miftakhul Cahyati, Sp.PM sebagai penguji sidang skripsi yang telah
memberikan masukan, saran dan semangat sehingga penulis dapat
menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
ix
6. Secara khusus penghargaan terimakasih yang tak terhingga kepada papa
Handoyo, mama Toni Ambar Krismayanti, dan Muhammad Mahdi
Bramasta tercinta atas segala doa, perhatian, dukungan baik secara moril
dan materil yang selalu diberikan untuk penulis.
7. Muhammad Zaqi Zakaria yang selalu memberi semangat, mendoakan
dan membantu banyak hal bagi penulis hingga penyelesaian skripsi ini
berjalan lancar.
8. Sahabat-sahabat terbaik (Azizah dan Anna) yang selalu mendukung,
semoga sukses bareng ya.
9. Teman satu kelompok (Elsa, Dyan, Anisa) dalam pembuatan skripsi yang
membantu banyak hal semoga bisa sukses bareng ya.
10. Teman-teman FKG angkatan 2014 dan seluruh keluarga besar FKG
beserta seluruh pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu per satu
yang telah mendoakan, mendukung, dan membantu kelancaran
penyusunan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna.
Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca
sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap
semoga tulisan ini bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca.
Malang, 14 Maret 2018
Penulis
x
DAFTAR ISI
Halaman Judul .....………..………..……………….…………………….………….. i
Halaman Persetujuan…………..……………………………….…………..……….. ii
Kata Pengantar……………………………………………………………………….. iii
Abstrak ….……………..………………………………………………………….…… v
Abstract ….…………………………………………………………………………… vi
Daftar Isi ..………………....…….…………………………………………………… vii
Daftar Gambar .………….…………………………………………………………… xi
Daftar Tabel .……………………………………………………………………….… xii
Daftar Lampiran …………………………….……………………………..……..… xiii
Daftar Singkatan …………………...……….…………………………....……...… xiv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang……………………………….………………………….. 1
1.2 Rumusan Masalah……………………………………………………… 3
1.3 Tujuan Penelitian….……………………………………………………. 4
1.3.1 Tujuan Umum …………………………………………………… 4
1.3.2 Tujuan Khusus ………………………………………………..… 4
1.4 Manfaat Penelitian………..………………………………….…….....… 5
1.4.1 Manfaat Akademik ...................................................................... 5
1.4.2 Manfaat Umum ............................................................................ 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Ulkus Traumatik ………..................................................................... 6
2.1.1 Definisi ………………..…….…..………………….......................... 6
2.1.2 Etiologi ……….……...................................................................... 6
2.1.3 Insidensi ……………………….………………………...….....……. 7
2.1.4 Gambaran Klinis ….……...………….…..…………..…….….…..... 8
2.2 Penyembuhan Luka …….……………..………………...……….......… 8
2.2.1 Definisi ….………………………...…………..….……….….….…… 8
2.2.2 Proses Penyembuhan Luka ......................................................... 9
2.3 Limfosit …………………….............................................................. 13
xi
2.4 Delima ….…………………............................................................... 16
2.4.1 Taksonomi ….………...…………….…..……..….…..….….….…… 17
2.4.2 Morfologi ..................................................................................... 18
2.4.3 Kandungan dan komposisi ………..….………………...…..…….. 19
2.4.3.1 Tanin ………………………………...….……………...….….…... 20
2.4.3.2 Flavonoid ……………………………….……..………….….….... 22
2.5 Triamcinolone acetonid 0.1% …………........................................... 23
2.6 Tikus Putih (Rattus norvegicus) .……….......................................... 25
BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN
3.1 Kerangka Konsep …………………………..……………………….. 27
3.2 Hipotesis Penelitian ……………………..…………………………… 28
BAB IV METODE PENELITIAN
4.1 Rancangan dan Desain Penelitian …........................................ 29
4.2 Sampel Penelitian…................................................................... 30
4.2.1 Jumlah Sampel Penelitian ....................................................... 30
4.2.2 Kriteria Sampel Penelitian ....................................................... 31
4.3 Variabel Penelitian .................................................................... 32
4.3.1 Variabel Bebas .…….……..…………………..……………..…. 32
4.3.2 Variabel Terikat ….....………………….…………....……...…... 32
4.3.3 Variabel Kontrol ..….………………………………..……............. 32
4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian ..................................................... 32
4.5 Bahan dan Alat/Instrumen Penelitian ........................................ 33
4.5.1 Perawatan dan pembuatan Makanan Hewan Coba................. 33
4.5.2 Bahan dan Alat untuk Membuat Ulserasi ................................ 33
4.5.3 Bahan dan Alat Pembuatan Ekstrak Kulit Delima.................... 33
4.5.4 Bahan dan Alat Pembuatan Gel Ekstrak Kulit Delima.............. 33
4.5.5 Bahan dan Alat Perlakuan……..……..……............................... 34
4.5.6 Bahan dan Alat Pengambilan & Pembuatan Preparat ............ 34
4.6 Definisi Operasional ................................................................... 34
4.6.1 Gel Ekstrak Kulit Buah Delima …………….…...……….……… 34
4.6.2 Ulkus Traumatik ………..………..…..…………..…..…………… 35
4.6.3 Jumlah Sel Limfosit …………….………...………...…….….…… 35
xii
4.7 Prosedur Penelitian/Pengumpulan Data .................................... 35
4.7.1 Kelaikan Etik …….…….……………..…………….……….…..... 35
4.7.2 Alur Penelitian ………….……..…………………………..….…... 36
4.7.3 Pembuatan Ekstrak Kulit Buah Delima …....………..………..... 36
4.7.4 Pembuatan Gel Ekstrak Kulit Buah Delima ……..………....….. 37
4.7.5 Pembuatan Ulkus Traumatik ….…..………..…….………....….. 39
4.7.6 Pengaplikasian Gel Ekstrak Kulit Buah Delima …..….…....….. 39
4.7.7 Pembedahan Hewan Coba ….…………….……….…..……….. 39
4.7.8 Sanitasi Hewan Coba .……...………….………..………….….... 40
4.7.9 Pembuatan Preparat ….………….……....…….………….……. 40
4.7.10 Penghitungan Jumlah Limfosit ..……..……………………...….. 41
4.7.11 Kerangka Operasional Penelitian …….….………………….….. 42
4.8 Analisis Data................................................................................ 43
BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA
5.1 Hasil Penelitian……………..……………………..…………………. 44
5.2 Analisis Data…………………………..…………..…………………. 48
5.2.1 Uji Normalitas Data…… ….….…….…………………......……… 48
5.2.2 Uji Homogenitas Ragam …….………………………..………..… 49
5.2.3 Uji One Way ANOVA (Analysis of Varian) ….…………..……… 50
5.2.4Uji Post Hoc Tukey HSD …….……..…..………….………..……… 51
BAB VI PEMBAHASAN ……………….………………..………………………..… 53
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN ………...……………..………….……..….. 59
7.1 Kesimpulan……………………….……………………….……….… 59
7.2 Saran………………………..….………………………………....….. 59
Daftar Pustaka………………………………………………………….…….………. 61
Lampiran ………..…………………..………………………………….…….………. 65
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Ulkus Traumatik ……………………..………………..………….......... 6
Gambar 2.2 Fase Penyembuhan Luka …….…………….……............................. 9
Gambar 2.3 Gambaran Sel Limfosit dengan Pewarnaan HE .………………….. 13
Gambar 2.4 Buah, Pohon, dan Bunga Delima Putih..…………..………….......... 18
Gambar 2.5 Struktur Kimia Ellagic Acid ………………………............................. 22
Gambar 2.6 Struktur Kimia Flavonoid .…………………………………………….. 23
Gambar 2.7 Tikus Putih (Rattus norvegicus) Galur Wistar ……………….…….. 25
Gambar 4.1 Kerangka Desain Penelitian …………...…………………………….. 29
Gambar 4.2 Kerangka Operasional Penelitian ……………..…………………….. 42
Gambar 5.1 Gambaran limfosit pada preparat hari ke-3 ………….…………….. 45
Gambar 5.2 Gambaran limfosit pada preparat hari ke-5 ………….…………….. 46
Gambar 5.3 Gambaran limfosit pada preparat hari ke-7 ………….…………….. 47
Gambar 5.4 Diagram rerata jumlah limfosit tikus putih ………….………...…….. 47
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Komposisi Sel Darah Putih Manusia …….….……………………….…14
Tabel 2.2 Kandungan Masing-Masing Bagian Dari Delima .…….…..………… 19
Tabel 4.1 Formula Sediaan Gel Ekstrak Kulit Buah Delima .…….….………….. 38
Tabel 5.1 Rata-rata Jumlah Limfosit Tikus Putih .…….….………………………. 46
Tabel 5.2 Uji Normalitas .…….….……………………………………………….….. 49
Tabel 5.3 Uji Homogenitas Ragam .…….….………………………………………. 49
Tabel 5.4 Uji One Way ANOVA .…….….………………………………….……….. 50
Tabel 5.5 Uji Post Hoc Tukey HSD .…….….…………………………………….… 51
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Ulkus pada rongga mulut atau orang awam biasa menyebutnya sariawan,
merupakan penyakit di rongga mulut yang sering di jumpai. Ulkus traumatik
diartikan sebagai suatu kelainan yang berbentuk ulser pada mukosa rongga
mulut yang disebabkan oleh adanya trauma (Regezi et al., 2012). Gambaran
klinis pada ulkus traumatik dapat berupa ulkus dengan dasar kekuningan, tepi
yang berwarna merah, tanpa indurasi dan disertai dengan rasa sakit Tepi yang
berwarna merah pada lesi ulkus merupakan tanda terjadinya inflamasi. Pada
keadaan yang terjadi kerusakan jaringan, mekanisme tubuh akan mengupayakan
mengembalikan komponen-komponen jaringan yang rusak tersebut dengan
membentuk struktur baru dan fungsional sama dengan keadaan sebelumnya
(Cawson et.al., 2008).
Penyembuhan luka adalah proses penggantian jaringan yang rusak atau
mati oleh jaringan baru yang sehat yang terjadi melalui interaksi bermacam-
macam sel yang berbeda dengan mediator maktriks ekstraseluler, normalnya
terjadi dalam waktu 7-21 hari. Proses penyembuhan dibagi kedalam 3 fase yaitu
fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase maturasi. Fase inflamasi terjadi setelah
perlukaan sampai hari ke-3 atau ke-5 setelah terjadi perlukaan jaringan, dalam
fase inflamasi terdapat berbagai sel radang salah satunya sel limfosit (Kim et al.,
2013).
Peran limfosit adalah melepaskan limfokin yang sangat berpengaruh
pada proses inflamasi. Limfokin mempengaruhi agregasi dan kemotaksis
2
makrofag dalam proses penyembuhan luka (Robbins et.al., 2013). Limfosit akan
bermigrasi ke daerah luka pada hari ke-3, kemudian jumlahnya akan memuncak
di hari ke-5, dan pada hari ketujuh limfosit mengalami penurunan (Miksusanti,
2010). Fase inflamasi berakhir ditandai dengan menurunnya jumlah sel inflamasi
kemudian dilanjutkan fase proliferasi dan remodeling (Sugiaman, 2011; Primatika
et al., 2010).
Ulkus traumatik biasanya dapat hilang dalam beberapa hari jika
penyebabnya dihilangkan, namun jika trauma terjadi secara berulang dan tidak
diatasi, maka ulkus akan bertambah parah dan berkembang hingga bisa
berakibat terjadinya hiperplasia atau hiperkeratosis mukosa. Resiko ini tentu tidak
dapat disepelekan (Regezi et al., 2012). Saat ini penanganan ulkus traumatik
dengan menggunakan obat kortikosteroid topikal yaitu Triamcinolone acetonide
0,1% namun obat ini memiliki efek samping lokal pada kulit berupa atrofi,
purpura, hipersensitifitas dan kandidiasis oral (Rebel, 2010; Siebelt et.al., 2015).
Dengan pertimbangan resiko pada ullkus traumatik dan efek samping
Triamcinolone acetonide 0,1% maka salah satu alternatif pengobatan yang
mampu mengatasi ulkus traumatik secara aman dan memiliki efek samping
minimal adalah dengan menggunakan bahan alami. Seperti yang diketahui
belakangan ini masyarakat cenderung untuk menggunakan bahan alami yang
digunakan sebagai obat tradisional karena mudah didapat, biaya yang murah.
Kulit buah delima dapat menjadi alternatif pilihan sebagai obat tradisional untuk
mengobati luka berupa radang pada mukosa. Pada penelitian yang dilakukan
Hernawati (2015) kulit buah delima dapat dimanfaatkan sebagai obat sakit perut
karena cacing, perdarahan seperti wasir, batuk darah, perdarahan rahim, radang
tenggorokan, keputihan (leukorea), dan nyeri lambung. Selain itu pada penelitian
3
Ismail (2012) kulit buah delima mempunyai kandungan polifenol tertinggi yakni
berupa enzim tanin (ellagic acid) dan flavonoid jika dibandingkan buah jeruk,
anggur, cranberry, pir, nanas, apel, peach serta teh hijau. Tanin (Ellagic acid)
dan flavonoid mempunyai peranan yang penting dalam menyembuhkan luka,
yaitu dapat menstimulasi terbentuknya biosintesis kolagen dan menghambat
enzim siklooksigenase dan lipooksigenase pada reaksi inflamasi sehingga
migrasi sel radang (limfosit) pada area radang akan menurun yang
mengakibatkan penyembuhan luka akan semakin cepat (Pratiwi, 2011).
Hal tersebut menjadi alasan utama dari pengguanaan kulit buah delima,
selain sebagai pemanfaatan limbah yang dapat berdampak baik terhadap
lingkungan (Madhawati, 2012). Selain itu penggunaan ekstrak kulit buah delima
secara topikal direkomendasikan untuk jaringan nekrotik, luka insisi, dan luka
eksisi. Pada penelitian yang dilakukan Adiga (2010) penggunaan ekstrak kulit
buah delima secara topikal pada punggung tikus putih dalam bentuk gel,
memperoleh hasil peningkatan penyembuhan luka yang signifikan.
Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui pengaruh gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.)
terhadap jumlah limfosit pada proses penyembuhan ulkus traumatik tikus putih
(Rattus norvegicus) yang diinduksi panas.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dirumuskan adalah
sebagai berikut :
Bagaimanakah pengaruh gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum
L.) terhadap jumlah limfosit pada proses penyembuhan ulkus traumatik tikus
putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi panas ?
4
1.3. Tujuan Penelitian
1.3.1. Tujuan Umum
Mengetahui pengaruh gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.)
terhadap jumlah limfosit pada proses penyembuhan ulkus traumatik tikus putih
(Rattus norvegicus) yang diinduksi panas.
1.3.2. Tujuan Khusus
1. Menghitung dan membandingkan jumlah limfosit hari ketiga, kelima, dan
ketujuh pada proses penyembuhan ulkus traumatik tikus putih (Rattus
norvegicus) yang diinduksi panas dan tidak diberikan perlakuan.
2. Menghitung dan membandingkan jumlah limfosit hari ketiga, kelima, dan
ketujuh pada proses penyembuhan ulkus traumatik tikus putih (Rattus
norvegicus) yang diinduksi panas dan diberi perlakuan dengan topikal
triamcinolone acetonid 0,1%.
3. Menghitung dan membandingkan jumlah limfosit hari ketiga, kelima, dan
ketujuh pada proses penyembuhan ulkus traumatik tikus putih (Rattus
norvegicus) yang diinduksi panas dan diberikan perlakuan dengan topikal
gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.).
4. Menganalisa perbedaan jumlah sel limfosit pada kelompok yang tidak
diberikan perlakuan, diberi perlakuan dengan topikal triamcinolone
acetonid 0.1%, dan yang diaplikasikan topikal gel ekstrak kulit buah
delima (Punica granatum L.) pada hari ke-3, 5, 7
1.4. Manfaat Penelitian
1.4.1. Manfaat Akademik
Menambah ilmu pengetahuan tentang pengaruh gel ekstrak kulit buah
delima (Punica granatum L.) terhadap jumlah limfosit pada proses penyembuhan
5
ulkus traumatik tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi panas, serta dapat
sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan obat
alamiah penyembuhan ulkus traumatik berupa topikal gel ekstrak kulit buah
delima (Punica granatum L.) yang efektif dan aman di bidang kedokteran gigi.
1.4.2. Manfaat Umum
Memberikan informasi ilmiah dan alternatif pengobatan kepada
masyarakat mengenai penggunaan bahan obat alamiah dari topikal gel ekstrak
kulit buah delima (Punica granatum L.) untuk menyembuhan ulkus traumatik.
.
6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Ulkus Traumatik
2.1.1 Definisi
Secara umum definisi dari Ulser atau ulkus itu sendiri adalah suatu
kerusakan lapisan epitel yang berbatas jelas yang membentuk cekungan yang
sering ditemukan di rongga mulut. Ulkus traumatikus diartikan sebagai suatu
kelainan yang berbentuk ulser pada mukosa rongga mulut yang disebabkan oleh
adanya trauma (mekanik, thermal, maupun kimiawi) (Regezi et al., 2012).
Gambar 2.1 : Ulkus Traumatikus (Neville, 2009)
2.1.2 Etiologi
Trauma karena mekanik seperti menggigit bibir, pipi atau lidah,
mengonsumsi atau mengunyah makanan keras, gigitan dari tonjolan gigi yang
tajam, trauma dari gigi yang patah dan iritasi gigi tiruan serta tumpatan yang
tajam (Delong & Burkhart, 2008). Dalam perawatan dental dapat terjadi trauma
pada jaringan lunak secara tidak sengaja. Ulkus dapat diakibatkan oleh cotton
rolls, tekanan saliva ejector yang tinggi atau instrumen bur yang mengenai
jaringan lunak (Regezi et al., 2012).
7
Trauma karena bahan kimia dapat diakibatkan oleh penggunaan
sejumlah kecil obat misalnya aspirin (chemical burn), yang kontak langsung
dengan mukosa, iritasi akibat penggunaan pasta gigi, mouthwash, dan bahan
bleaching (Delong & Burkhart, 2008).
Trauma karena thermal (suhu) disebabkan karena terpapar atau kontak
dengan api, cairan panas atau objek-objek panas lainnya (Regezi et al., 2012).
Selain itu juga bisa karena makanan atau minuman yang panas. Luka yang
berhubungan dengan thermal food burns biasanya tampak pada palatum atau
mukosa bukal posterior. Lesi tampak sebagai zona eritema dan ulserasi
biasanya muncul pada epitel yang nekrotik (Neville, 2009).
2.1.3 Insidensi
Prevalensi ulkus traumatik cukup tinggi dibandingkan lesi-lesi mulut
lainnya yaitu sebesar (15,6%), setelah varises dasar mulut (59,6%), dan fissured
tongue (28%) (Delong & Burkhart, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh
Castellanos, dkk. pada tahun 2003 di Meksiko terhadap 1000 orang
menunjukkan prevalensi ulkus traumatik sebesar 40,24% (Castellanos et al.,
2008). Cebeci, dkk. dalam penelitiannya pada tahun 2005 di Turki mendapati
prevalensi ulkus traumatik mencapai 30,47% (Cebeci et al., 2009).
Ulkus traumatik memang biasanya dapat hilang dalam beberapa hari jika
penyebabnya dihilangkan, namun jika trauma terjadi secara berulang dan tidak
diatasi, maka ulkus akan bertambah parah. Trauma kronis pada mukosa mulut
dapat menyebabkan ulkus akan berkembang hingga bisa berakibat terjadinya
hiperplasia atau hiperkeratosis mukosa. (Regezi et al., 2012).
8
2.1.4 Gambaran Klinis
Ulkus dimulai dengan luka seperti melepuh di jaringan mulut yang
berbentuk bulat atau oval. Setelah beberapa hari, luka tersebut pecah dan
menjadi berwarna putih ditengahnya dibatasi dengan daerah kemerahan. Bila
berkontak dengan makanan dengan rasa yang tajam seperti pedas atau asam
akan terasa sakit dan perih serta aliran saliva menjadi meningkat. Ulkus di dalam
mulut biasanya dibagian mukosa labial, mukosa bukal, lidah, dan gusi. Ulkus
menimbulkan rasa sakit dan rasa terbakar yang terjadi satu sampai dua hari yang
kemudian menimbulkan luka di rongga mulut. Luka ulkus agak kaku dan sangat
peka terhadap gerakan lidah atau mulut sehingga rasa sakit atau rasa panas
yang dirasakan ini menyebabkan kesulitan makan, minum, ataupun bicara. Rasa
sakit akibat ulkus biasanya akan hilang antara 7 sampai 10 hari dan lesi ini akan
sembuh dan jika lebih perlu dilakukan pemeriksaan biposi (Cawson et.al., 2008).
2.2 Penyembuhan Luka
2.2.1 Definisi
Luka didefinisikan sebagai kerusakan pada jaringan tubuh oleh karena
adanya jejas baik fisik maupun kimia yang dapat menyebabkan gangguan
kontinuitas yang normal dari struktur jaringan dalam tubuh. Jejas fisik yang dapat
menyebabkan kerusakan jaringan antara lain : trauma oleh benda tajam atau
tumpul, insisi, temperatur yang ekstrim, radiasi, dan obstruksi aliran darah.
Sedangkan jejas kimia seperti aspirin burn dan phenol burn. Luka terjadi karena
rusaknya struktur dan fungsi anatomis normal akibat proses patologis yang
berasal dari internal maupun eksternal yang mengenai organ tertentu. Efek yang
akan muncul ketika terdapat luka antara lain kehilangan seluruh atau sebagian
9
fungsi organ, perdarahan dan pembekuan darah, kontaminasi bakteri serta
kematian sel. Luka yang tidak sembuh dalam waktu yang lama dikhawatirkan
mengalami komplikasi (Setyarini et.al., 2013).
Luka pada jaringan tubuh makhluk hidup dapat dimungkinkan menjadi
salah satu media bagi mikroba patogen untuk berkembang biak, dan pada
akhirnya akan menginfeksi luka tersebut. Tubuh memiliki kemampuan untuk
menghilangkan atau menghambat proses infeksi tersebut dengan tujuan untuk
mempertahankan keutuhan jaringan. Tubuh memiliki seluler dan biokimia untuk
memperbaiki integritas jaringan dan kapasitas fungsional akibat adanya luka
yang biasa disebut dengan proses wound healing (Permatasari dkk., 2012).
2.2.2 Proses Penyembuhan Luka
Penyembuhan luka merupakan suatu proses kompleks berupa pergantian
sel-sel jaringan yang telah mati dengan sel-sel jaringan yang masih hidup (Kumar
et al., 2013). Sifat penyembuhan bervariasi bergantung pada lokasi, keparahan
dan luas luka (Hardjito et al., 2012). Penyembuhan luka bertujuan untuk
mengembalikan struktur dan fungsi jaringan yang terluka melalui 3 tahap/fase:
inflamasi, proliferasi, dan remodeling (Kim et al., 2013).
Gambar 2.2 A. Fase inflamasi. B. Fase proliferasi. C. Fase maturasi/remodelling
(Yusuf, 2014)
10
a. Fase Inflamasi
Fase inflamasi terjadi saat mulai awal terjadinya luka sampai hari ke-3 atau
ke-5 setelah terjadinya luka. Diawali dengan infiltrasi pada daerah jejas oleh
netrofil yang berfungsi untuk menghambat infeksi mikroorganisme. Netrofil
bertugas memfagositosis dan menghancurkan bakteri, partikel asing, dan
jaringan rusak. Netrofil tertarik menuju daerah luka antara 24 – 36 jam luka oleh
agen-agen kemoatraktif, termasuk TGF-β, komplementer seperti C3a dan C5a,
dan peptida formylmethionyl yang dihasilkan bakteri dan produk-produk platelet.
Bersama dengan regulasi dari molekul permukaan adhesi, netrofil menjadi
lengket dan melalui proses marginasi sel-sel endotel pada kapiler di sekitar luka.
Netrofil berputar di sepanjang permukaan endotel yang didorong maju oleh aliran
darah. Proses adhesi dan berputar dimediasi oleh interaksi selectin-dependent
dan termasuk perlekatan lemah. Pada fase inflamasi juga muncul sel makrofag
pada 48-72 jam setelah luka dan muncul di sekitar luka, kemudian melanjutkan
proses fagositosis. Sel-sel tersebut berasal dari monosit yang menuju luka untuk
menjadi makrofag (Kumar et al., 2013).
Sel terakhir yang memasuki daerah luka merupakan sel-sel limfosit, 72
jam setelah luka dengan mengaktivasi interleukin-1 (IL-1), kemudian jumlahnya
akan memuncak pada hari ke-5 dan menurun pada hari ke-7, komponen
komplemen dan immunoglobulin G (IgG) yang melepas produk-produk.
Interleukin-1 (IL-1) berperan dalam kolagenase yang dibutuhkan untuk
remodeling kolagen, memproduksi komponen-komponen matriks ekstraseluler
dan degradasinya (Kumar et al., 2013).
Inflamasi merupakan respon yang melibatkan sel-sel host, pembuluh
darah, dan protein mediator untuk menghilangkan penyebab jejas dan berguna
11
dalam penyembuhan luka. Respon proteksi diawali dengan melekat, merusak,
dan menetralisir agen-agen seperti mikroba ataupun toxin. Jejas berturut-turut
mengalami penyembuhan luka dan memperbaiki daerah tersebut. Tanpa adanya
inflamasi, infeksi tidak dapat terkontrol dan luka tidak akan sembuh, sehingga
inflamasi berperan sebagai imunitas utama dalam respon proteksi terhadap luka
(Yusuf, 2014).
b. Fase Proliferasi
Yang terjadi pada fase proliferasi atau fase fibroplastik adalah epitelisasi,
angiogenesis, pembentukan jaringan granulasi, dan deposisi kolagen.
Merupakan fase yang terjadi pada hari ke 2–21 setelah terjadi perlukaan yang
ditandai dengan proliferasi jaringan ganulasi pada daerah luka. Jaringan
granulasi merupakan kombinasi dari elemen seluler termasuk fibroblas, kapiler,
fibronektin, dan asam hyaluronik (Kumar et al., 2013).
Pada fase ini, luka dipenuhi oleh sel radang, fibroblas, dan kolagen,
membentuk jaringan berwarna kemerahan dengan permukaan berbenjol halus
yang disebut jaringan granulasi. Epitel tepi luka yang terdiri atas sel basal
terlepas dari dasarnya dan berpindah mengisi permukaan luka. Tempatnya
kemudian diisi oleh sel baru yang terbentuk dari proses mitosis. Proses migrasi
hanya terjadi ke arah yang lebih rendah atau datar. Proses ini baru berhenti
setelah epitel saling menyentuh dan menutup permukaan luka. Pada saat
permukaan luka sudah tertutup, proses fibroplasia dengan pembentukan jaringan
granulasi juga akan terhenti dan mulailah proses pematangan dalam fase
remodelling (Neck et al., 2012).
12
c. Fase Maturasi / Remodelling
Fase ini dimulai pada minggu ketiga setelah perlukaan dan berakhir sampai
kurang lebih 1-1,5 tahun. Pada fase ini terjadi pematangan dan penyerapan
kembali jaringan yang berlebih. Fase ini dapat berlangsung berbulan-bulan dan
dinyatakan berakhir bila semua tanda radang sudah lenyap. Proses ini diawali
dengan migrasi keratinosit dari basal membran ke permukaan (Reinke, 2012).
Proses reepitelisasi, remodeling dan proses migrasi dipicu oleh MMPs.
Degradasi proteolitik dari matriks ekstraseluler merupakan bagian penting dari
proses repair dan remodeling luka, tetapi tingginya kadar MMPs dapat juga
mendegradasi matriks ekstraseluler, mencegah migrasi dan pertautan sel. Pada
level sel, keseimbangan terletak pada sintesis komponen matriks ekstraseluler
dan degradasi oleh protease. Proses regulasi diperankan oleh growth factor
termasuk didalamnya platelet-derived growth factor (PDGF), transforming growth
factor-β (TGF- β), fibroblast growth factor, dan vascular endothelial growth factor
13 (Imuro et al., 2008).
Fase remodeling mempunyai dua karakter yaitu kontraksi dari luka dan
remodeling dari kolagen. Kontraksi dari luka disebabkan adanya miofibroblas
pada luka yang berinteraksi secara spesifik dengan matriks kolagen. Sedangkan
proses remodeling dari kolagen dimulai dengan menurunnya kolagen tipe III
yang kemudian digantikan oleh kolagen tipe I. Proses degradasi ini dimediasi
oleh matriks metalloprotein. Pada fase awal remodeling tensile strength dari luka
hanya sekitar 20 % dari kulit normal dan berangsur – angsur meningkat hingga
70 % dari kulit normal pada akhir fase (Neck et al., 2012).
13
2.3 Limfosit
Limfosit merupakan elemen kunci dalam produksi imun. Setelah lahir,
beberapa limfosit terbentuk di sumsum tulang. Namun, sebagian besar terbentuk
di kelenjar getah bening, timus, limpa dan dari sel prekursor yang berasal dari
sumsum tulang dan diproses di timus. Limfosit memasuki aliran darah untuk
sebagian besar melalui sistem limfatik. Pada waktu tertentu, hanya sekitar 2%
dari limfosit tubuh berada dalam darah perifer. Sebagian besar sisanya berada di
organ limfoid (Kumar et al., 2013).
Gambar 2.3 Gambaran mikroskop cahaya perbesaran 400x sel limfosit dengan pewarnaan HE (haematoxylin-eosin) (Meilawaty, 2011)
Peran limfosit pada inflamasi kronis adalah sebagai respon humoral dan
seluler. Limfosit mengikat antigen, lalu akan teraktivasi dan mengeluarkan
limfokin salah satunya IFN-γ. Limfokin berperan dalam stimulasi dan aktivasi
makrofag dalam melakukan fagositosis. Makrofag yang teraktivasi akan
melepaskan sitokin, yaitu IL-1 dan TNF. Limfosit dan makrofag saling
merangsang satu sama lain secara persisten untuk mampu menghilangkan agen
antigen pemicu dan sel fibroblas telah membentuk jaringan yang kuat (Robbins
et.al., 2013).
14
Limfosit akan bermigrasi ke daerah luka pada hari ke-3, kemudian
jumlahnya akan memuncak di hari ke-5, dan pada hari ketujuh limfosit
mengalami penurunan (Miksusanti, 2010). Limfosit dalam darah berukuran
sangat bervariasi sehingga pada pengamatan sediaan apus darah dibedakan
menjadi: limfosit kecil (7-8 μm), limfosit sedang dan limfosit besar (12 μm).
Jumlah limfosit menduduki nomer 2 setelah netrofil yaitu sekitar 1500-4000 per
mm3 darah atau 20-40% dari seluruh leukosit. Di antara 3 jenis limfosit, limfosit
kecil terdapat paling banyak. Limfosit kecil ini mempunyai inti bulat yang kadang-
kadang bertakik sedikit. Intinya gelap karena khromatinnya berkelompok dan
tidak nampak nukleolus. Sitoplasmanya yang sedikit tampak mengelilingi inti
sebagai cincin berwarna biru muda. Kadang-kadang sitoplasmanya tidak jelas
mungkin karena butir-butir azurofil yang berwarna ungu. Limfosit kecil kira-kira
berjumlah 92% dari seluruh limfosit dalam darah (Kumar et al., 2013).
Tabel 2.1 : Komposisi sel darah putih manusia (Robbins et.al., 2013).
Sel / μl (Rata-rata)
Batas Normal Persentase jumlah total sel darah putih
Total seluruh darah putih 9000 4000 – 11000
Neutrofil 5400 3000-6000 50-70
Eosinofil 275 150-300 1-4
Basofil 35 0-100 0.4
Limfosit 2750 1500-4000 20-40
Monosit 540 300-600 2-8
15
Terdapat tiga kelompok limfosit yang dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu :
1. Limfosit B
Di bawah mikroskop cahaya dengan pewarnaan HE, morfologi Limfosit T
dan B tidak dapat dibedakan Limfosit B merupakan sel yang berasal dari sel
stem di dalam sumsum tulang dan tumbuh menjadi sel plasma, yang
menghasilkan antibodi. Jumlah sel B limfosit adalah 25% dari total keseluruhan
limfosit tubuh. Limfosit B mampu menghasilkan berbagai jenis antibodi yang
digunakan untuk melawan antigen. Sel ini memiliki reseptor-reseptor pada
permukaannya untuk antigen tertentu (Robbins et.al., 2013).
2. Limfosit T
Limfosit T merupakan sel yang berasal dari kelenjar timus. Ada tiga bentuk
sel T, yaitu sel T helper (CD4+), T supresor (Ts), dan T cytotoksik (CD8+). Sel T
helper (CD4+) merupakan sel T yang berperan dalam stimulasi sintesis antibodi
dan aktivasi makrofag dengan cara mengsekresikan molekul yang disebut
sitokinin. Sel ini bekerja bersama dengan aktivitas antibodi sel B. Sel T supresor
(Ts) berperan menekan aktivitas sel T yang lain. Sel ini mempunyai aktivitas
dapat menurunkan produksi antibodi. Sel cytotoksik (CD8+) memiliki kemampuan
untuk menghancurkan sel alogenik dan sel sasaran yang terinfeksi patogen
intraseluler. Limfosit T merupakan limfosit predominan walau limfosit B juga
ditemukan pada jaringan perlukaan kulit manusia sebagai sel-sel imun adaptif
(Robbins et.al., 2013).
3. Limfosit NK ( Natural Killer )
Limfosit ini memiliki ukuran yang agak lebih besar daripada limfosit T dan B.
Limfosit ini juga dikenal sebagai Large Granular Lymphocyte (LGL) karena
16
merupakan sel dengan sejumlah besar sitoplasma dengan granula azurofilik
(Robbins et.al., 2013).
Limfosit dan makrofag berperan penting karena saling keterikatan satu sama
lain pada fase inflamasi penyembuhan luka. Makrofag melepas antigen terhadap
sel T, menghasilkan kostimulator dan sitokin yang telah distimulasi oleh sel T
(Kumar et al., 2013). Penelitian Zaky (2017) menunjukkan limfosit mengalami
penurunan setelah diberi pemberian Triamcinolone acetonide pada hari ke 7 dan
telah aktif pada hari sebelumnya, yakni hari ke 3 yang menunjukkan pemberian
antiinflamasi dapat efektif dalam mempengaruhi limfosit. Limfosit dalam
penyembuhan luka berfungsi dalam produksi interferon yang akan meningkatkan
agregasi makrofag dan nantinya akan menghasilkan faktor-faktor pertumbuhan
serta berperan dalam meningkatkan fagositosis. Makrofag yang terkativasi oleh
interferon yang dihasilkan limfosit akan mengalami peningkatan dalam
pembentukan Nitric Oxide (NO) dan Reactive Oxygen SPesies (ROS) yaitu
protein yang berperan dalam fagositosis. Faktor-faktor pertumbuhan yang
dihasilkan makrofag dapat menyebabkan proliferasi fibroblas dan angiogenesis
sehingga terjadi penyembuhan luka (Kumar et al., 2013). Saat luka mengalami
perbaikan, limfosit di dalam jaringan akan mengalami penurunan dikarenakan sel
radang termasuk limfosit digantikan oleh fibroblas sehingga jumlah sel fibroblas
mengalami peningkatan (Hardiono, 2012).
2.4 Delima (Punica granatum L.)
Delima (Punica granatum Linn) nama ini diambil dari bahasa Latin yaitu
dari Ponus dan Granatus merupakan salah satu jenis tanaman berbiji yang
buahnya dikonsumsi di seluruh dunia. Diperkirakan tanaman ini berasal dari
Persia dan daerah Himalaya yang terletak di selatan India. Sumber kuno
17
mengatakan bahwa selama ribuan tahun delima sudah dibudidayakan di
Pakistan, Cina, India timur, Persia (Modern Iran), serta budidayanya telah
membentang melalui wilayah Mediterania ke perbatasan Eropa Turki dan
Amerika, California serta Meksiko (Ismail et.a.l, 2012).
Tanaman ini bisa berbuah sepanjang tahun, dan dapat tumbuh hingga
mencapai tinggi 8 meter, tergantung jenis buahnya ada yang berwarna putih,
merah dan ungu atau hitam. Delima sering ditanam sebagai tanaman hias,
tanaman obat, atau tanaman buah. Pemanfaatan delima sebagai tanaman obat
sebenarnya sudah ada sejak jaman Mesir kuno (Hernawati., 2015).
2.4.1 Taksonomi
Taksonomi delima menurut Hernawati, 2015 adalah sebagai berikut :
Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Subkelas : Rosidae
Ordo : Myrtales
Famili : Lythraceae
Genus : Punica
Species : Punica granatum L
18
2.4.2 Morfologi
Gambar 2.4 : Buah, pohon, dan bunga delima putih (Ismail et al, 2012)
Tumbuhan delima (Punica granatum L.) merupakan tanaman semak atau
perdu meranggas yang dapat tumbuh dengan tinggi mencapai 5- 8 meter.
Tanaman buah delima tersebar mulai dari daerah subtropik hingga tropik, dari
dataran rendah hingga ketinggian di bawah 1000 mdpl. Tanaman ini sangat
cocok untuk ditanam di tanah yang gembur dan tidak terendam oleh air, serta air
tanahnya tidak dalam (Madhawati, 2012).
Batang tanaman delima berbentuk kayu ranting yang bersegi, dan
percabangan banyak tetapi lemah. Pada ketiak daunnya, terdapat duri dan
warnanya coklat. Daunnya tunggal dengan tangkai yang pendek dan letaknya
berkelompok. Daun delima memiliki bentuk yang lonjong dengan pangkal yang
lancip, ujung tumpul, tepi rata, pertulangan menyirip, dan permukaan mengkilap.
Panjang daun bisa mencapai 1-9 cm dengan lebar 0,5-2,5 cm (Savitri, 2008).
19
Delima dapat berbunga sepanjang tahun, bunganya tunggal dengan
tangkai pendek, serta keluar di ujung ranting atau ketiak daun yang paling atas.
Bunga delima biasanya 1-5 kuntum berada di ujung ranting, berlilin, panjang dan
lebarnya masing-masing 4-5 cm, daun kelopak dan penyangganya sama-sama
2-3 cm panjangnya. Bunga delima biasanya berwarna merah, putih dan ungu.
Warna bunga dapat menentukan warna daging buah delima di dalamnya
(Madhawati, 2012).
2.4.3 Kandungan dan Komposisi
Sari buah dan kulit buah delima telah terbukti memiliki aktivitas
antioksidan. Fakta ini berhubungan dengan kemampuan kandungan dalam
delima yang berperan sebagai anti inflamasi. Berikut adalah zat-zat penting yang
terkandung dalam delima.
Tabel 2.2 : Kandungan masing-masing bagian dari delima (Ismail, 2012; Hayouni, 2011)
Bagian Tumbuhan Kandungan Manfaat
Kulit Batang Tanin
Flavonoid
Alkaloid
Anti-neoplastik
Anti-HIV
Anti-oksidan
Daging Buah Tanin
Flavonoid
Alkaloid
Glukosa
Fruktosa
Sukrosa
Anti-neoplastik
Pencerah Warna Kulit
Anti-viral
Anti-Mutagenik
Anti-oksidan
Anti- Inflamatori
Hepatoprotektif
Kulit Buah Tanin
Flavonoid
Anti-viral
Anti-oksidan
Anti-hipertensi
Anti-neoplastik
Pencerah warna kulit
20
Anti- HIV
Anti-Mutagenic
Anti-Inflamatori
Anti-bacterial
Daun Tanin
Flavonoid
Hypolipidemic
Anti-oksidan
Hepatoprotective
Anti-viral
Anti-hipertensi
Anti-neoplastik
Pencerah warna kulit
Anti-mutagenik,
Akar Alkaloid Anti-neoplastik
Bunga Tanin Anti-viral
Anti-neoplastik
Pencerah warna kulit
Anti-mutagenik
Anti-inflamatori
Batang Tanin Anti-neoplastik
Dari tabel diatas dapat dilihat kulit buah delima memiliki kandungan
komponen fenol yang substansial yaitu flavonoid (anthocyanins, cathecin) dan
tanin (punicalin, pedunculagin, punicalagin, gallic, dan ellagic acid). Semua
komponen ini terdapat dalam kulit buah delima, dimana sebanyak 92% aktivitas
antioksidan, anti kanker dan antiinflamasi banyak didapatkan pada kulit delima.
Kulit buah delima ini memiliki efek antiinflamasi yang lebih tinggi dibandingkan
buah dan bijinya (Ismail et al, 2012).
2.4.3.1 Tanin
Pada proses penyembuhan luka, tanin berperan sebagai anti radikal
bebas dan antimikroba yang membantu dalam kontraksi luka dan peningkatan
kecepatan epitelisasi. Radikal bebas dapat menjadi salah satu faktor yang
21
menyebabkan tertundanya penyembuhan luka. Oleh karena itu, ekstrak herbal
yang mengandung antioksidan dan antimikroba bisa menjadi terapi yang baik
untuk mempercepat penyembuhan luka (Thakur et al., 2011).
Tanin merupakan senyawa yang paling banyak ditemukan pada
berbagai bagian dari delima. Kandungan tanin dalam delima yaitu punicalin,
pedunculagin, punicalagin ellagic acid, gallic acid, dan anthocyanidin,. Dimana
Ellagic acid merupakan kandungan tanin yang dominan pada kulit buah delima
(Thresianty, 2013).
Ellagic acid salah satu bahan aktif dari buah delima yang memiliki
aktivitas antioksidan, anti bakteri, anti virus dan aktivitas antiinflamasi. Ellagic
acid berperan dalam antiinflamasi dengan cara menstimulasi proliferasi
pembuluh darah dan meningkatkan sintesis TGF‐β yang menstimulasi
terbentuknya biosintesis kolagen (Pratiwi, 2011).
Fungsi lain dari ellagic acid yaitu dapat melindungi kerusakan sel
karena radikal bebas. Kemampuan ini secara sinergis mengalami peningkatan
apabila dikombinasi dengan komposisi lain dari buah delima yang juga berfungsi
sebagai anti oksidan yang cukup kuat , yaitu anthocyanidin. Anthocyanidin
merupakan anti oksidan terbukti membantu memperbaiki fungsi pembuluh darah.
Fungsi bahan aktif buah delima sebagai anti mikroba dan mampu memperbaiki
fungsi pembuluh darah akan mempercepat proses penyembuhan dari ulkus
traumatik (Ghalayani, 2013).
22
Gambar 2.5 Struktur Kimia Ellagic Acid (Thresianty, 2013)
2.4.3.2 Flavonoid
Flavonoid adalah suatu golongan metabolit sekunder yang tersebar
merata dalam dunia tumbuh-tumbuhan, termasuk salah satu golongan fenol alam
terbesar dalam tumbuh-tumbuhan. Rasa kesat pada buah delima disebabkan
kandungan flavonoid yang tinggi (Weston, 2013).
Penelitian secara in vivo maupun in vitro menunjukkan bahwa flavonoid
memiliki aktivitas biologis maupun farmakologis, antara lain bersifat antibakteri,
anti inflamasi, anti alergi, antikarsinogen, antioksidan, dan melindungi pembuluh
darah (Laszlo, 2015).
Flavonoid bersifat antibakteri karena mampu berinteraksi dengan DNA
bakteri sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding sel
bakteri, mikrosom, dan lisosom. Flavonoid sebagai anti inflamasi karena dapat
menghambat pelepasan asam arakidonat dan sekresi enzim lisosom dari sel
netrofil dan sel endothelial, dan menghambat fase proliferasi. Terhambatnya
pelepasan asam arakidonat dari sel inflamasi akan menyebabkan kurang
tersedianya substrat arakidonat bagi jalur siklooksigenase dan jalur
lipoksigenase, yang pada akhirnya akan menekan jumlah prostaglandin dan
leukotrien. Penekanan prostaglandin sebagai mediator inflamasi dapat
menyebabkan berkurangnya nyeri dan pembengkakan, mengurangi terjadinya
23
vasodilatasi pembuluh darah dan aliran darah lokal, sehingga migrasi sel radang
pada area radang akan menurun. Menurunnya jumlah leukotrien (LTB4), akan
mengurangi kemotaktsis leukosit polimorfonuklear dan adhesi PMN serta limfosit
ke dinding endotel, sehingga jumlah sel PMN dan limfosit pada area radang akan
menurun (Pratiwi, 2011).
Flavonoid mempunyai kemampuan antioksidan terhadap radikal bebas.
Kemampuan antioksidasi dari setiap flavonoid pada prinsipnya berdasarkan
struktur senyawanya. Flavonoid berperan penting dalam menjaga permeabilitas
serta meningkatkan resistensi pembuluh darah kapiler, oleh karena itu flavonoid
digunakan pada keadaan patologis seperti terjadinya gangguan permeabilitas
dinding pembuluh darah. Terjadinya kerusakan pembuluh darah kapiler akibat
jejas menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler, sehingga darah (terutama
plasma darah) akan keluar dari kapiler ke jaringan, diikuti dengan terjadinya
respons inflamasi (Weston, 2013).
Gambar 2.6 Struktur Kimia Flavonoid (Thresianty, 2013)
2.5 Triamcinolone acetonid 0,1%
Triamcinolone acetonide 0,1 % dental paste adalah golongan kortikosteroid
topikal yang memiliki efek antiinflamasi dan analgesik sehingga dapat
mempercepat penyembuhan ulser dan mengurangi keparahan lesi. Obat ini
diindikasikan untuk pengobatan lesi inflamasi mulut dan lesi ulseratif.
24
Kontraindikasi penggunaan Triamcinolone acetonide 0,1 % dental paste adalah
pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap kortikosteroid. Jika pasien
mengalami hipersensitivitas, maka penggunaan obat harus dihentikan. Efek
samping penggunaan obat ini dapat menyebabkan kandidiasis oral (Siebelt et.al.,
2015)
Kortikosteroid merupakan hormon steroid yang dihasilkan oleh korteks
adrenal yang pembuatan bahan sintetik analognya telah berkembang dengan
pesat. Penggunaan preparat kortikosteroid ini dimulai pertama kali di Amerika,
kurang lebih 50 tahun yang lalu berupa hidrokortison. Sejak itu, berbagai
spektrum produk dihasilkan dan berbagai upaya dilakukan agar efek
terapeutiknya meningkat tetapi efek sampingnya berkurang. Efek utama
penggunaan kortikosteroid secara topikal ialah efek vasokonstriksi, efek
antiinflamasi dan efek antimitosis (Rebel, 2010).
Kortikosteroid topikal adalah golongan obat yang efektif digunakan untuk
menurunkan gejala inflamasi pada berbagai kondisi kulit. Dibanding dengan
kortikosteroid oral, senyawa kortikosteroid topikal mempunyai afinitas yang tinggi
terhadap reseptornya dan juga mengalami inaktifasi (biotransformasi) yang cepat
dan efisien di hati, sehingga efek sistemiknya yang minimal. Hal ini dikarenakan
rendahnya bioaviabilitas oral dari senyawa tersebut, yaitu untuk masing-masing
kortikosteroid mempunyai bioaviabilitas sebagai berikut : Hidrokortison (40-70%),
Prednison (60-100%), Dexametasone (49-99%), Metilprednisolone (53-83%),
Flunisolide (21%), Budesonide (11-13%), Triamcolone (22%) (Scully, 2008).
Resiko terberat (walaupun sangat jarang terjadi) penggunaan
kortikosteroid topikal adalah penekanan aksis adrenal-hipotalamus akibat
absorbsi sistemik. Selain itu, dapat pula terjadi glaukoma. Yang lebih kerap
25
terjadi adalah efek samping lokal pada kulit berupa atrofi, purpura dan perubahan
warna kulit. Efek samping ini secara langsung bergantung pada potensi
kortikosteroid dan lama serta cara penggunaannya (Rebel, 2010).
2.6 Tikus Putih ( Rattus norvegicus)
Menurut Depkes (2011), klasifikasi dari tikus putih (Rattus norvegicus)
adalah :
Kingdom : Animalia Order : Rodentia
Phylum : Chordata Family : Muridae
Subphylum : Vertebrata Genus : Rattus
Class : Mammalia Species : Norvegicus
Gambar 2.7 Tikus putih (Rattus norvegicus) galur Wistar (Al-Hajj et al., 2016)
Hewan percobaan atau hewan laboratorium adalah hewan yang sengaja
dipelihara dan diternakan untuk dipakai sebagai hewan model guna mempelajari
dan mengembangkan berbagai macam bidang ilmu dalam skala penelitian atau
pengamatan laboratorik. Penggunaan hewan percobaan untuk penelitian banyak
dilakukan di bidang fisiologi, farmakologi, biokimia, patologi, dan komparatif
zoologi. Di bidang ilmu kedokteran selain untuk penelitian, hewan percobaan
juga sering digunakan sebagai keperluan diagnostik. Berbagai jenis hewan yang
umum digunakan sebagai hewan percobaan, yaitu mencit, tikus, marmut, kelinci,
26
hamster, unggas, kambing, domba, sapi, kerbau, kuda, dan simpanse
(Sulistiawati, 2011).
Tikus putih (Rattus norvegicus) strain wistar dipilih sebagai sampel
karena sifat-sifatnya yaitu, mudah dipelihara, dan merupakan hewan yang relatif
sehat dan cocok untuk berbagai penelitian. Ciri-ciri morfologi Rattus norvegicus
antara lain memiliki berat 150-600 gram, hidung tumpul dan badan besar dengan
panjang 18-25 cm, kepala dan badan lebih pendek dari ekornya, serta telinga
relatif kecil dan tidak lebih dari 20-23 mm (Depkes, 2011).
Selain alasan tersebut, para peneliti akan memilih tikus putih dalam
penelitian karena ukuran tikus yang besar sehingga membuat penanganan,
pengambilan sampel dan melakukan prosedur lebih mudah (Phillips, 2013).
Hampir semua gen manusia yang terkait penyakit saat ini yang kita kenal
memiliki gen yang setara dalam genom tikus, sehingga tikus menjadikannya alat
penelitian yang cocok. Penyakit tersebut adalah obesitas dan diabetes, kanker,
penyakit kardiovaskular (termasuk tekanan darah tinggi dan gagal jantung),
penyakit neurologis (seperti penyakit Parkinson), penyakit imun dan inflamasi
(Wendy, 2015)
Kelebihan tikus putih dibandingkan binatang percobaan yang lain antara
lain bersifat omnivora (pemakan segala), mempunyai jaringan dan kebutuhan gizi
yang hampir sama dengan manusia. Selain itu dari segi ekonomi harganya
murah dan umumnya lebih cepat berkembang biak (Phillips, 2013).
27
BAB III
KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN
3.1. Kerangka Konsep
Keterangan :
= Variabel yang diteliti
= Variabel yang tidak diteliti
= Efek dari gel ekstrak kulit delima
= Meningkat karena pengaruh kandungan ellagic acid dan flavonoid
= Menurun karena pengaruh kandungan ellagic acid dan flavonoid
Fase Inflamasi
Fase Proliferasi
Gel Ekstrak Kulit Buah Delima
- Flavonoid
- Tanin (Ellagic acid)
Ulkus Traumatik
Aktivasi
Makrofag ↑ Jumlah ↓
Aktivasi ↑
Limfosit
IFN-ү
Fase Remodelling
Epitelisasi ↑ Fibroblas ↑ Angiogenesis ↑
KGF IL-6
Kolagen ↑
Penyembuhan Luka ↑
PGF, TGF-β1
EGF, IGF2, TGF-α, IL-1
FGF, VeGF
28
Pembahasan :
Penyembuhan ulkus terdiri dari 3 fase yaitu fase inflamasi, proliferasi dan
remodelling. Rangkaian fase tersebut akan dimulai segera setelah terjadinya
ulkus. Fase inflamasi berlangsung pada hari ke 0-5 setelah terjadi ulkus. Pada
fase inlamasi ini terjadi aktivasi sel-sel inflamasi, salah satunya adalah limfosit.
Limfosit akan mengikat antigen, lalu akan teraktivasi dan mengeluarkan limfokin
salah satunya IFN-γ. Limfokin berperan dalam stimulasi dan aktivasi makrofag
dalam melakukan fagositosis. Makrofag yang teraktivasi akan melepaskan
berbagai faktor-faktor pertumbuhan yang dapat menyebabkan proliferasi
fibroblast, epitelisasi dan angiogenesis sehingga terjadi penyembuhan luka.
Gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) mengandung
senyawa flavonoid dan tanin (ellagic acid). Ellagic acid merupakan senyawa
yang paling banyak ditemukan pada kulit buah delima yang bersifat antibakteri,
antivirus dan antiinflamasi. Ellagic acid berperan dalam antiinflamasi dengan
cara menstimulasi proliferasi pembuluh darah dan meningkatkan sintesis TGF‐β
yang menstimulasi terbentuknya biosintesis kolagen sehingga penyembuhan
luka juga akan meningkat. Flavonoid bersifat antiinflamasi karena dapat
menghambat pelepasan asam arakidonat yang pada akhirnya akan menekan
jumlah prostaglandin dan leukotrien. Menurunnya jumlah prostaglandin dan
leukotrien akan mengurangi kemotaktsis leukosit polimorfonuklear seta limfosit
ke dinding endotel, sehingga jumlah sel PMN dan limfosit pada area radang akan
menurun. Menurunnya jumlah limfosit menandakan proses inflamasi cepat
selesai yang nantinya akan digantikan dengan proses proliferasi dan remodelling
sehingga akan mempercepat penyembuhan luka.
29
3.2. Hipotesis Penelitian
Ho dari penelitian ini adalah gel ekstrak kulit buah delima (Punica
granatum) tidak berpengaruh terhadap jumlah sel limfosit pada proses
penyembuhan ulkus traumatik tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi
panas.
H1 dari penelitian ini adalah gel ekstrak kulit buah delima (Punica
granatum) berpengaruh terhadap jumlah sel limfosit pada proses penyembuhan
ulkus traumatik tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi panas.
30
BAB IV
METODE PENELITIAN
4.1. Rancangan dan Desain Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen murni
(True Experimental) menggunakan rancangan penelitian “Post Test Only
Randomized Control Group Design” di laboratorium secara in-vivo. Jenis
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian gel ekstrak kulit buah
delima (Punica granatum L.) terhadap jumlah limfosit pada proses penyembuhan
ulkus traumatik tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi panas.
Gambar 4.1. Kerangka Desain Penelitian
Keterangan :
S :sampel R : random K(-)3 : kelompok kontrol negatif tanpa diberi perlakuan sampai hari ke-3 pasca diinduksi panas
dan kemudian dilakukan pembedahan K(+)3 : kelompok kontrol positif diberi Triamcinolone acetonide 0,1% yang diaplikasikan 2x
sehari selama 3 hari pasca diinduksi panas dan kemudian dilakukan pembedahan satu hari setelah diberi perlakuan
S R
K(-) 7
K(-) 3
Observasi
K(+) 3
P 3
K(+) 7
P 7
K(-) 5
K(+) 5
P 5
31
P3 : kelompok perlakuan diberi gel ekstrak kulit delima (Punica granatum L.)yang diaplikasikan 2 kali sehari selama 3 haripasca diinduksi panas dan kemudian dilakukan pembedahan satu hari setelah diberi perlakuan
K(-)5 : kelompok kontrol negatif tanpa diberi perlakuan sampai hari ke-5 pasca diinduksi panas dan kemudian dilakukan pembedahan
K(+)5 : kelompok kontrol positif diberi Triamcinolone acetonide 0,1% yang diaplikasikan 2 kali sehari selama 5 hari pasca diinduksi panas dan kemudian dilakukan pembedahan satu hari setelah diberi perlakuan
P5 : kelompok perlakuan diberi gel ekstrak kulit delima (Punica granatum L.) yang diaplikasikan 2 kali sehari selama 5 hari pasca diinduksi panas dan kemudian dilakukan pembedahan satu hari setelah diberi perlakuan
K(-)7 : kelompok kontrol negatif tanpa diberi perlakuan sampai hari ke-7 pasca diinduksi panas dan kemudian dilakukan pembedahan
K(+)7 : kelompok kontrol positif diberi Triamcinolone acetonide 0,1% yang diaplikasikan 2 kali sehari selama 7 hari pasca diinduksi panas dan kemudian dilakukan pembedahan satu hari setelah diberi perlakuan
P7 : kelompok perlakuan diberi gel ekstrak kulit delima (Punica granatum L.) yang diaplikasikan 2 kali sehari selama 7 hari pasca diinduksi panas dan kemudian dilakukan pembedahan satu hari setelah diberi perlakuan
4.2. Sampel Penelitian
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih jantan
(Rattus norvegicus) yang berumur 3 bulan dengan berat 180-200 gram yang
dipelihara di Laboratorium Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
Malang.
4.2.1. Jumlah Sampel Penelitian
Pada penelitian ini terbagi menjadi 9 kelompok sampel. Menurut Hanani
tahun 2005, jumlah sampel tiap perlakuan didapatkan dari rumus (n - 1) (t - 1) ≥
15, Dari rumus tersebut maka diperoleh hasil perhitungan :
Keterangan :
t= jumlah kelompok
n= jumlah pengulangan
Pada penelitian ini t=9, oleh karena itu, perhitungan menjadi :
(n – 1) (t – 1) 15 8n – 8 15
(n-1) (9-1) 15 n 2,8
(n – 1) 8 15
32
Pada penelitian ini digunakan minimal 3 tikus putih untuk tiap
kelompoknya. Penelitian ini dibagi menjadi sembilan kelompok perlakuan,
sehingga dibutuhkan 27 tikus putih. Untuk mengurangi lost of sample di tengah-
tengah penelitian karena tikus putih mati, maka jumlah sampel ditambah 3 ekor
menjadi 30 ekor tikus putih.
4.2.2. Kriteria Sampel Penelitian
Kriteria Inklusi sampel penelitian yang digunakan yaitu:
1. Tikus putih galur Wistar keturunan murni
2. Berjenis kelamin jantan
3. Sehat dan belum pernah digunakan untuk penelitian
4. Umur 3 bulan
5. Berat badan 180-200 gram
Kriteria Ekslusi sampel penelitian yang digunakan yaitu:
1. Tikus sakit selama masa adaptasi (tikus putih tidak bergerak aktif)
2. Tikus mati selama penelitian berlangsung
4.3. Variabel Penelitian
4.3.1. Variabel bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah gel ekstrak kulit buah delima
(Punica granatum L.).
4.3.2. Variabel terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah jumlah sel limfosit saat proses
penyembuhan pada tikus putih (Rattus novegicus) yang telah diinduksi panas.
33
4.3.3. Variabel kontrol
Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah :
1. Genetik (Tikus putih galur Wistar keturunan murni)
2. Jenis kelamin jantan (untuk menghindari efek hormonal yang lebih dominan
pada tikus betina)
3. Usia (3 bulan)
4. Berat badan (180-200 gram)
5. Makanan dan minuman yang dikonsumsi objek penelitian
6. Kemungkinan adanya infeksi
4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Farmasi, Laboratorium
Biokimia dan Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas
Brawijaya Malang pada bulan Desember 2017 - Febuari 2018
4.5 Bahan dan Alat/Instrumen Penelitian
4.5.1. Perawatan dan Pembuatan Makanan Hewan Coba
Alat perawatan hewan coba meliputi 27 buah box plastik ukuran 15 x 35 x
45 cm3 dengan tutup kandang dari anyaman kawat, botol air, sekam dan satu
neraca Sartorius untuk menimbang berat badan hewan coba. Bahan makanan
hewan adalah pellet (pakan tikus).
4.5.2. Bahan dan alat untuk membuat ulserasi
Alat yang dibutuhkan semen stopper, spiritus burner, pinset bedah, dan
kaca mulut. Bahan yang dibutuhkan ketamine 0.2 ml, cotton pellet, masker, dan
34
sarung tangan, tikus putih wistar jantan (Rattus norvegicus) umur 3 bulan dengan
berat 180-200 gram.
4.5.3 Bahan dan alat pembuatan ekstrak kulit buah delima (Punica
granatum L.)
Alat yang dibutuhkan pisau, kertas saring, tabung Erlenmeyer, alat
evaporator. Bahan yang dibutuhkan kulit buah delima (Punica granatum L.),
ethanol 96%, dan aquadest.
4.5.4. Bahan dan alat pembuatan gel ekstrak kulit buah delima (Punica
granatum L.)
Alat yang dibutuhkan mortar, pengaduk, alat penimbangan digital dan
tube. Bahan yang dibutuhkan ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.),
propilenglikol, carbopol, metil paraben, gliserin, Trietanolamin (TEA), masker,
sarung tangan dan aquadest.
4.5.5. Bahan dan alat perlakuan
Alat yang dibutuhkan cotton bud, masker, dan sarung tangan. Bahan
yang dibutuhkan gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.),
Triamcinolone acetonid 0.1%, Tikus putih (Rattus norvegicus) umur 3 bulan
dengan berat 180-200 gram yang diinduksi panas dengan ujung cement stopper
alat kedokteran gigi sehingga terdapat ulkus pada mukosanya.
4.5.6. Bahan dan alat pengambilan jaringan dan pembuatan preparat
Alat yang dibutuhkan scalpel, microtom, kaca obyek dan penutup, blok
paraffin, waterbath, tempat pewarna dan cucian, kertas saring, timer, dan kuas
kecil. Bahan yang dibutuhkan eter, formalin 10 %, aceton, xylol, gelatin, alkohol
96%, Pewarna Haematoxylin dan Eosin, dan Lithium carbonat.
35
4.6 Definisi Operasional
4.6.1. Gel Ekstrak Kulit Buah Delima
Ekstrak kulit buah delima adalah sediaan pekat yang didapat dengan
mengekstrak zat aktif kulit buah delima dengan metode maserasi menggunakan
pelarut etanol 96%. Bagian tanaman yang digunakan adalah kulit buah tanpa
ada kriteria khusus mengenai berat dan ukuan yang dipergunakan. Kemudian
ekstrak kulit buah delima dibuat menjadi gel dengan menggunakan bahan
carbopol, propilenglikol, metil paraben, TEA (trietanolamin), gliserin, dan
aquadest hingga terbentuk gel ekstrak kulit buah delima dengan konsentrasi
100%. Pada penelitian ini menggunakan kulit buah delima jenis lokal yang
diperoleh dari Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dan
diidentifikasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur UPT Medica Batu.
4.6.2. Ulkus Traumatik
Ulkus traumatik dalam penelitian ini adalah ulkus yang dibuat dengan
cara menempelkan semen stopper dengan penampang ± 1.5 mm yang telah
dipanaskan hingga membara selama 10 detik pada mukosa labial bawah tikus
selama 3 detik tanpa tekanan sehingga didapatkan ulkus dengan diameter ±1.5
mm berbentuk ovoid, berwana putih kekuningan dan dikelilingi eritema, yang
nantinya akan diaplikasikan gel ekstrak kulit buah delima secara topikal.
4.6.3. Jumlah Sel Limfosit
Penghitungan jumlah limfosit adalah penghitungan jumlah sel limfosit
pada preparat eksisi biopsi jaringan sekitar ulser pada hari ke-3, ke-5, ke-7 pasca
ulserasi dengan pewarnaan haematoxylin-eosin dan diamati dengan mikroskop
cahaya dengan perbesaran mikroskop 400 kali per 5 lapang pandang dan
36
kemudian dibuat foto preparat. Limfosit dalam pewarnaan HE akan tampak
berwarna ungu pada bentuk nukleus yang besar dan bulat berinti satu,
sitoplasmanya yang sedikit tampak mengelilingi inti sebagai cincin berwarna biru
muda.
4.7. Prosedur Penelitian/Pengumpulan Data
4.7.1 Kelaikan Etik
Penelitian ini diawali dengan pengurusan ethical clearance di Komisi Etik
Penelitian Bioscience Universitas Brawijaya.
4.7.2 Alur Penelitian
Sebelum ulserasi pada mukosa labial, sejumlah tikus putih dilakukan
adaptasi di laboratorium dengan dikandangkan pada box plastik berukuran 15 x
35 x 45 cm3 yang ditutup dengan kawat kassa dengan dasar sekam yang diganti
setiap 3 hari sekali dan diberi pakan standar selama 7 hari. Setelah 7 hari masa
adaptasi, mukosa labial tikus putih dianastesi dengan ketamine 0.2 ml secara
intramuscullar, kemudian jika tikus putih tidak memberi respon saat diberi
rangsangan rasa sakit menggunakan pinset bedah maka tikus putih bisa
diinduksi panas dengan ujung semen stopper sehingga terbentuk ulkus, lalu
diberikan analgesik novalgin sebanyak 0.3 ml diberikan secara intramuscular,
kemudian dimasukkan kedalam kandang yang telah diberi label kelompok kontrol
negatif K(-), kelompok kontrol positif K(+), kelompok perlakuan (P). Satu kandang
terdiri dari 1 ekor tikus. Kemudian dilakukan pembedahan pada hewan coba
pada H+1 setelah diberi perlakuan time series yaitu pada hari ke 3, 5, dan 7.
Kemudian membuat preparat untuk menghitung jumlah sel limfosit, analisis data
dan membuat kesimpulan (Pusat penelitian dan Pengembangan Peternakan,
2016).
37
4.7.3 Pembuatan Ekstrak Kulit Buah Delima (Punica granatum L.)
Kulit buah delima yang masih segar dikirim ke Dinas Kesehatan UPT
Medica Batu untuk dilakukan identifikasi dan pembuatan ekstrak. Kulit buah
delima yang masih segar dicuci dengan air hingga bersih kemudian dikeringkan
hingga benar-benar kering dengan cara diangin-anginkan dalam ruangan,
digiling hingga halus dengan menggunakan alat giling khusus sehingga
didapatkan serbuk dan ditimbang sebanyak 500 gram serbuk kulit buah delima.
Proses pembuatan ekstrak dengan teknik maserasi yaitu dengan cara serbuk
kulit buah delima dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer, kemudian
ditambahkan ethanol 96% sebanyak 4000 mL. Tabung erlenmayer ditutup rapat
dan diaduk dengan homogenizer selama 30 menit dan disimpan pada suhu
kamar dan didiamkan selama 24 jam sambil sesekali dilakukan pengadukan
untuk meratakan konsentrasinya. Setelah 24 jam campuran itu disaring dengan
kertas filter, proses ini diulang 2 kali hingga diperoleh hasil berupa ampas dan
filtrat, hasil filtrat dievaporasi dengan vacuum rotary evaporation selama 4 jam
guna memisahkan pelarut ethanol dengan ekstrak ethanol kulit buah delima.
Filtrat dievaporasi dengan pengurangan tekanan pada suhu yang diatur sesuai
dengan titik didih ethanol hingga semua pelarut terpisah. Didapatkan hasil akhir
yang akan digunakan dalam percobaan yaitu ekstrak ethanol kulit buah delima
dengan konsentrasi 100% dari pelarut enatol 96% yang telah dipisahkan dengan
berat sebesar 58 gram (Hedaputra, 2014).
4.7.4 Pembuatan Gel Ekstrak Kulit Buah Delima (Punica granatum L.)
Menimbang terlebih dahulu semua bahan yang akan digunakan ke dalam
pembuatan gel ekstrak kulit buah delima sesuai takaran. Setelah semua bahan
ditimbang sesuai takaran kemudian karbopol dikembangkan dengan aquadest
38
dalam mortir hingga mengembang. Metil paraben dilarutkan dalam gliserin aduk
hingga larut dalam beaker gelas. Pada mortir yang berbeda ekstrak etanol kulit
buah delima digerus hingga teksturnya menjadi lembut lalu tambahkan sebagian
propilenglikol lalu gerus hingga homogen. Setelah karbopol mengembang gerus
terlebih dahulu dengan di tambahkan TEA sedikit- sedikit untuk membuat pH
sediaan gel sedikit basa kemudian gerus hingga membentuk basis gel.
Campuran gliserin dan metil paraben ditambahkan dalam basis gel sambil di
gerus hingga homogen. Sisa propilenglikol ditambahkan dalam campuran basis,
gerus hingga homogen. Campurkan gerusan ekstrak ke dalam basis gel dan
gerus sampai homogen. Ditambahkan aquadest yang sudah dipanaskan sedikit
sedikit sampai 40 ml. Kemudian setelah gel ekstrak kulit buah delima selesai
dibuat gel dimasukan ke dalam tube tertutup yang terlindung dari kontaminasi
luar dan ditimbang untuk mengetahui berat gelnya. Didapatkan hasil akhir
penimbangan gel ekstrak kulit buah delima sebanyak 44.67 gram.
Gel tersebut lalu disimpan pada suhu kamar selama 24 jam untuk
mengamati sifat fisik gel (pengamatan organoleptis meliputi homogenitas, pH
dan daya sebar). Uji organoleptis bertujuan untuk mengetahui apakah ada
perubahan warna, bentuk, dan bau selama penyimpanan. Uji pH bertujuan untuk
mengetahui adanya perubahan pH yang mungkin terjadi selama penyimpanan
yang akan berpengaruh terhadap stabilitas gel. Untuk memenuhi syarat sediaan
gel yang baik dan dapat diterima masyarakat dapat dilihat dari sifat fisik dan
stabilitasnya. Sifat fisik yang diukur adalah daya sebar gel. Uji homogenitas
dilakukan dengan mengoleskan zat yang akan diuji pada sekeping kaca harus
menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar.
(Supomo, 2016)
39
Tabel 4.1. Formula Sediaan Gel Ekstrak Kulit Buah Delima (Punica granatum L.)
(Maulina, 2015)
Komponen Takaran (gram)
Ekstrak Etanol Kulit Buah Delima 4 g
Karbopol 2 g
Gliserin 4 g
Propilenglikol 2 g
Metil paraben 0,06 g
Trietanolamin (TEA) 2 g
Aquadest 40 g
4.7.5 Pembuatan Ulkus Traumatik
Pembuatan ulkus traumatik yang diinduksi panas didahului dengan
anastesi menggunakan ketamine 0.2 ml secara intramuscular, kemudian
diinduksi dengan ujung cement stopper kedokteran gigi dengan penampang ±
1.5 mm yang sebelumnya telah dipanaskan dengan bunsen selama 10 detik dan
ditempelkan pada mukosa labial bawah tanpa tekanan selama 3 detik sehingga
terbentuk ulkus dengan diameter ±1.5 mm berbentuk ovoid, berwana putih
kekuningan dan dikelilingi eritema, yang nantinya akan diaplikasikan gel ekstrak
kulit buah delima secara topikal. Setelah dilakukan pembuatan ulkus traumatik
kemudian tikus putih diberi analgesik novalgin 0.3 ml secara intramuscular untuk
mengurangi rasa sakit pada tikus putih pasca di ulserasi (Pusat penelitian dan
Pengembangan Peternakan, 2016).
4.7.6 Pengaplikasian Gel Ekstrak Kulit Buah Delima (Punica granatum L.)
Setelah satu hari ulserasi, pada kelompok perlakuan dilakukan aplikasi
gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) dua kali sehari. Sedangkan
pada kelompok kontrol positif dilakukan aplikasi Triamcinolone acetonide 0,1%
40
selama dua kali sehari dengan hanya satu kali oles dan kelompok kontrol negatif
tidak diberi perlakuan. Pengaplikasian gel ekstrak kulit delima (Punica granatum
L.) dilakukan secara topikal menggunakan cotton bud. Dilakukan aplikasi yang
sama pada kelompok kontrol (+) dan (-) pada hari ketiga, kelima sampai hari
ketujuh.
4.7.6. Pembedahan Hewan Coba
Pada satu hari setelah hari ke 3, 5, dan 7 hewan coba dikorbankan
dengan teknik dislokasi leher. Setelah itu, dilakukan pembedahan untuk
mengambil jaringan sekitar ulser pada hewan coba. Jaringan tersebut kemudian
dibersihkan dengan NaCl 0.9% fisiologis dan dimasukkan ke dalam botol organ
yang sudah berisi larutan BNF (Buffered Neutral Formalin) 10% dengan pH 6.5-
7.5 (Pusat penelitian dan Pengembangan Peternakan, 2016).
4.7.7. Sanitasi Hewan Coba
Semua sisa organ hewan coba yang sudah dibedah dan tidak terpakai
dilakukan sanitasi. Tubuh tikus yang tersisa dibersihkan dan dilakukan antiseptik
dengan alkohol 70%. Semua sisa organ tikus yang sudah dibedah dan tidak
terpakai kemudian dikubur dengan mengubur di halaman belakang laboratorium
biokimia dengan membuat lubang dengan kedalaman 100 cm dan dibalut kain
atau bahan yang mudah terurai. Sampah dari prosedur pembedahan yang tidak
terpakai dibuang dalam satu kantong plastik, sampah medis dipisahkan
tersendiri, dan diserahkan ke Rumah Sakit Saiful Anwar untuk proses
pembuangan. Area kerja sisa pembedahan dibersihkan dengan sabun dan jika
perlu disemprot dengan alkohol.
41
4.7.8. Pembuatan preparat
a. Fiksasi
Pada tahap fiksasi, dilakukan perendaman jaringan ulser pada larutan
formalin 10% selama 18-24 jam, kemudian jaringan dicuci dengan aquadest
selama 15 menit.
b. Embedding
Jaringan ulkus dimasukkan pada beberapa cairan yaitu aceton selama 1
jam x 4, Xylol selama ½ jam x 4, paraffin cair selama 1 jam x 3 dan penanaman
jaringan kulit pada paraffin blok.
c. Slicing
Blok yang sudah tertanam jaringan ulkus diletakkan pada balok es
selama kurang lebih 15 menit kemudian blok ditempelkan pada cakram microtom
rotary kemudian sayat jaringan ulkus secara vertikal dengan ukuran 4 mikron.
Sayatan jaringan ulkus yang dibentuk pita diambil dengan menggunakan kuas
kecil, kemudian letakkan pada water bath yang mengandung gelatin dengan
suhu 36ᵒC. Setelah sayatan jaringan ulkus merentang, sayatan diambil dengan
mmenggunakan object glass dan didiamkan selama 24 jam.
d. Staning
Object glass dimasukkan dalam Xylol selama 15 menit x 3, alkohol 96%
selama 15 menit x 3, kemudian dicuci dengan air mengalir selama 15 menit.
Setelah itu object glass dimasukkan pada pewarna Haematoxylin selama 15
menit dan dicuci dengan air mengalir selama 15 menit.Object glass dimasukkan
pada Litium carbonat selama 20 detik dan dicuci dengan air mengalir selama 15
menit. Selanjunya object glass dimasukkan pada pewarnaan Eosin selama 15
42
menit, alkohol 96% selama 15 menit x 3 dan Xylol selama 15 menit x 3. Dan
yang terakhir, preparat ditutup dengan menggunakan deck glass Entellan.
4.7.9. Penghitungan Jumlah Limfosit
Sel limfosit pada sediaan preparat jaringan dihitung dan diamati
menggunakan mikrometer okuler pada mikroskop cahaya dengan perbesaran
mikroskop 400 kali per 5 lapang pandang. Tiap potongan jaringan jumlah limfosit
dihitung secara sistematis mulai dari pojok kiri bawah kemudian digeser kekanan
dan ditarik keatas demikian seterusnya sehingga semua lapang pandang
terbaca. Kemudian dihitung limfosit dari masing-masing kelompok potongan
jaringan tersebut lalu dibandingkan percepatan penyembuhan dalam hitungan
hari dari jumlah limfosit antara kelompok kontrol (-), (+), dan kelompok perlakuan.
43
4.7.10 Kerangka Operasional Penelitian
Gambar 4.2 Kerangka Operasional Peneltian
Aklimatisasi selama 7 hari
Mukosa oral bagian labial tikus di induksi panas sehingga terbentuk ulkus
K(-)3
Kel.tanpa
diberi perla kuan dan di biarka
n sampai hari ke 3
Pembuatan Preparat Histologi Jaringan
Pengamatan dan Perhitungan Jumlah Limfosit
Analisa Data
27 Ekor Tikus Putih
K(-)5
P3
K(-)7
P5
P7
Kel.tanpa
diberi perla kuan
dan di biarka
n sampai hari ke 5
Kel.tanpa
diberi perlakuan
dan di biarka
n sampai hari ke 7
Kel.pemberian gel
ekstrak kulit
delima dan di biarkan sampai hari ke
5
Kel.pemberian gel
ekstrak kulit
delima dan di biarkan sampai hari ke
3
Kel.pemberian gel
ekstrak kulit
delima dan di
biarkan sampai hari ke
7
Di dekaputasi H+1 pada hari ke-3, ke-5 dan ke-7
K(+)3
K(+)5
K(+)7
Kel.pemberian
Triamcinolone
acetonide 0,1% dan di
biarkan sampai
hari ke 3
Kel.pemberian Triamcinolone acetonide 0,1% dan di biarkan sampai hari ke
5
Kel.pemberian
Triamcinolone
acetonide 0,1% dan di biarkan sampai
hari ke 7
44
4.8. Analisa Data
Pada penelitian dilakukan uji normalitas untuk menginterpretasikan
apakah suatu data memiliki sebaran normal atau tidak dan uji homogenitas untuk
menguji berlaku atau tidaknya asumsi ANOVA, yaitu apakah data yang diperoleh
dari setiap perlakuan memiliki varian yang homogen. Uji normalitasnya
menggunakan uji Shapiro-Wilk karena besar sampelnya ≤50 kemudian dilakukan
uji homogenitas ragam menggunakan Levene’s test. Apabila data yang diperoleh
berdistribusi normal (signifikansi > 0,05) dan homogenitas ragam terpenuhi
(p>0,05), maka digunakan uji One Way Anova sebagai uji hipotesisnya (Dahlan,
2011).
Uji one way Anova bertujuan untuk mengetahui perbedaan limfosit
antara kelompok tanpa perlakuan, aplikasi gel ekstrak kulit buah delima (Punica
granatum L) pada proses penyembuhan ulkus traumatik mukosa tikus putih
(Rattus norvegicus) yang diinduksi panas. Apabila data berdistribusi tidak normal
dan varian data tidak homogen maka digunakan uji Kruskal Wallis. Selanjutnya,
dilakukan uji Post Hoc Tukey sebagai lanjutan one way Anova atau Mann
Whitney sebagai uji lanjutan Kruskal Wallis (Dahlan, 2011).
45
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA
5.1 Hasil Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian gel
ekstrak kulit buah delima (Punica granatum Linn) terhadap jumlah sel limfosit
pada penyembuhan luka ulkus traumatik pada tikus putih (Rattus norvegicus)
yang diinduksi panas.
Pada penelitian ini menggunakan hewan coba berupa tikus putih (Rattus
norvegicus) yang kemudian dibagi menjadi 9 kelompok, yaitu kelompok kontrol
negatif hari ke-3 K(-) 3, kelompok kontrol negatif hari ke-5 K(-) 5, kelompok
kontrol negatif hari ke-7 K(-) 7, kelompok kontrol positif hari ke-3 K(+) 3,
kelompok kontrol positif hari ke-5 K(+) 5, kelompok kontrol positif hari ke-7 K(+)
7, kelompok perlakuan hari ke-3 P (3), kelompok perlakuan hari ke-5 P (5),
kelompok perlakuan hari ke-7 P (7). Kelompok kontrol negatif K(-) merupakan
kelompok yang dilakukan ulserasi pada mukosa labial menggunakan ujung
semen stopper yang telah dipanaskan dan tidak diberikan perlakuan. Kelompok
kontrol positif K(+) merupakan kelompok yang dilakukan ulserasi kemudian
diaplikasikan Triamcinolone acetonide 0,1%, sedangkan kelompok perlakuan (P)
merupakan kelompok yang dilakukan ulserasi kemudian diaplikasikan gel ekstrak
kulit buah delima (Punica granatum Linn). Perlakuan dilakukan satu hari setelah
induksi panas dilakukan karena ulser telah terbentuk. Tampak gambaran lesi
ulser bebentuk bulat atau oval dengan diameter 1,5 mm, dasar lesi berwarna
putih kekuningan atau putih pucat, dikelilingi oleh pinggiran kemerahan.
46
Sampel didapatkan dengan mengambil jaringan mukosa labial tikus putih
(Rattus norvegicus) yang didekaputasi setelah hari ketiga, kelima, ketujuh pasca
ulserasi kemudian dilakukan pembuatan preparat dengan pengecatan
Haematoxylin-Eosin. Pengamatan dan perhitungan jumlah sel limfosit dilakukan
dengan menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran 400 kali,
didapatkan gambaran limfosit berwarna keunguan. Limfosit dalam pewarnaan
HE akan tampak berwarna ungu pada bentuk nukleus yang besar dan bulat
berinti satu, sitoplasmanya yang sedikit tampak mengelilingi inti sebagai cincin
berwarna biru muda, ukuran limfosit yang ditemukan bervariasi dari sedang
hingga besar. Penghitungan jumlah limfosit dilakukan dengan cara manual
sebanyak 5 lapang pandang kemudian di rata-rata. Hasil penghitungan jumlah
sel limfosit tikus putih kontrol negatif, positif dan perlakuan dapat dilihat dalam
gambar 5.4
Gambar 5.1 Gambaran limfosit pada preparat hari ke-3 dengan pengecatan HE perbesaran 400x (a) Kelompok kontrol negatif (b) Kelompok kontrol positif (c) Kelompok perlakuan
(a) (b)
(c)
47
Berdasarkan (gambar 5.1) diatas didapatkan bahwa jaringan ulkus
traumatik pada mukosa labial tikus putih (Rattus norvegicus) pada kelompok
kontrol negatif pada H+3 tampak gambaran jumlah sel limfosit yang tinggi dan
kelompok perlakuan pada H+3 tampak gambaran jumlah sel limfosit yang
rendah.
Gambar 5.2 Gambaran limfosit pada preparat hari ke-5 dengan pengecatan HE perbesaran 400x (a) Kelompok kontrol negatif (b) Kelompok kontrol positif (c) Kelompok perlakuan
Berdasarkan (gambar 5.2) diatas didapatkan bahwa jaringan ulkus
traumatik pada mukosa labial tikus putih (Rattus norvegicus) pada kelompok
kontrol negatif pada H+5 tampak gambaran jumlah sel limfosit yang tinggi dan
kelompok perlakuan pada H+5 tampak gambaran jumlah sel limfosit yang
rendah.
(a) (b)
(c)
48
Gambar 5.3 Gambaran limfosit pada preparat hari ke-7 dengan pengecatan HE perbesaran 400x (a) Kelompok kontrol negatif (b) Kelompok kontrol positif (c) Kelompok perlakuan
Berdasarkan (gambar 5.3) diatas didapatkan bahwa jaringan ulkus
traumatik pada mukosa labial tikus putih (Rattus norvegicus) pada kelompok
kontrol negatif pada H+7 tampak gambaran jumlah sel limfosit yang tinggi dan
kelompok perlakuan pada H+7 tampak gambaran jumlah sel limfosit yang
rendah.
Gambar 5.4 Diagram rerata jumlah limfosit tikus putih (Rattus norvegicus) pada masing masing kelompok pada pemeriksaan mikroskop dengan perbesaran 400 kali sebanyak 5 lapang pandang.
8.3
13.2
6.46
4.6
8.7
2.4 3.4
7.3
1.86
0
2
4
6
8
10
12
14
Hari ke-3 Hari ke-5 Hari ke-7
Kontrol Negatif
Kontrol Positif
Perlakuan
(a)
(b)
(c)
49
Berdasarkan (gambar 5.4) menunjukan bahwa pada hari ke-3 kelompok
kontrol negatif memiliki rata-rata jumlah limfosit tertinggi yaitu 8.3 dan kelompok
perlakuan memiliki rata-rata jumlah limfosit yang paling rendah yaitu 3.4. Pada
hari ke-5 kelompok kontrol negatif memiliki rata-rata jumlah limfosit tertinggi yaitu
13.2 dan kelompok perlakuan memiliki rata-rata jumlah limfosit terendah yaitu
7.3. Pada hari ke-7 kelompok kontrol negatif memiliki rata-rata jumlah limfosit
tertinggi yaitu 6.46 dan kelompok perlakuan memiliki rata-rata ketebalan epitel
terendah yaitu 1.86. Selain itu, dari diagram diatas didapatkan bahwa kelompok
kontrol negatif mengalami peningkatan jumlah limfosit pada hari ke-3 dan hari ke-
5 dan penurunan pada hari ke 7; kelompok kontrol positif mengalami
peningkatan jumlah limfosit dari hari ke-3 dan hari ke-5 kemudian menurun pada
hari ke-7; kelompok perlakuan mengalami peningkatan jumlah limfosit pada hari
ke-3 dan hari ke-5 dan penurunan pada hari ke 7.
5.2 Analisa Data
Data hasil penelitian berupa jumlah sel limfosit dianalisis menggunakan
metode one way Anova. Sebelum dilakukan pengujian dengan one way Anova,
dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas ragam. Uji normalitas menggunakan
Shapiro-Wilk dan uji homogenitas menggunakan Levene’s Test.
5.2.1 Uji Normalitas Data
Uji statistik pertama adalah untuk menentukan normalitas data dengan
menggunakan uji Shapiro-Wilk, dimana suatu data dikatakan memiliki sebaran
normal yang jika p > 0.05 (Dahlan, 2011). Didapatkan hasil pengujian normalitas
sebagai berikut
50
Tabel 5.2 : Uji Normalitas
Berdasarkan pada tabel diatas, didapatkan nilai signifikansi sebesar
0,084. Jika nilai signifikansi dibandingkan dengan p=0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Sehingga, dari
pengujian ini dapat diketahui bahwa uji normalitas telah terpenuhi dan data
berdistribusi normal.
5.2.2 Uji Homogenitas Ragam
Setelah mengetahui bahwa data terdistribusi normal, selanjutnya
menentukan apakah data jumlah limfosit memiliki varian yang berbeda atau tidak
dengan menggunakan uji homogenitas Levene’s Test. Pada uji homogenitas
Levene’s Test suatu data dikatakan memiliki varian normal bila nilai signifaksi p >
0.05 (Dahlan, 2011). Dari hasil analisis data didapatkan pengujian homogenitas
ragam sebagai berikut.
Tabel 5.3 : Uji Homogenitas Ragam
Berdasarkan pada tabel diatas, didapatkan koefisien Levene statistis
sebesar 2.305 dengan nilai signifikansi sebesar 0,067. Jika nilai signifikansi
Tests of Normality
.147 27 .138 .933 27 .084Sel Limfosit
Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Lilliefors Significance Correctiona.
Test of Homogeneity of Variances
Sel Limfos it
2.305 8 18 .067
Levene
Statistic df1 df2 Sig.
51
dibandingkan dengan p=0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi
lebih besar daripada 0,05. Sehingga, dari pengujian ini dapat diketahui bahwa uji
homogenitas ragam telah terpenuhi.
5.2.3 Uji One Way Anova (Analysis of Varian)
Setelah kedua pengujian yang melandasi uji one way Anova telah
terpenuhi, selanjutnya dilakukan uji one way Anova, yang bertujuan untuk
mengevaluasi perbedaan nilai jumlah limfosit antara kelompok, hipotesis
ditentukan melalui suatu rumusan yaitu Ho diterima bila nilai signifikansi lebih
dari 0,05. Ho dari penelitian ini adalah gel ekstrak kulit buah delima (Punica
granatum L.) tidak berpengaruh terhadap jumlah limfosit pada proses
penyembuhan ulkus traumatik pada tikus putih (Rattus norvegicus), sedangkan
H1 adalah gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) berpengaruh
terhadap jumlah limfosit pada proses penyembuhan ulkus traumatik pada tikus
putih (Rattus norvegicus). Berdasarkan uji statistik ini dapat diketahui apakah
terdapat perbedaan jumlah limfosit yang signifikan antar kelompok. Perbedaan
rata-rata limfosit dianggap bermakna jika nilai p < 0.05. Berikut hasil
penghitungan uji one way Anova.
Tabel 5.4 : Uji One Way Anova
ANOVA
Sel Limfosit
314.732 8 39.341 13.817 .000
51.253 18 2.847
365.985 26
Between Groups
Within Groups
Total
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
52
Berdasarkan pada tabel diatas, didapatkan signifikansi sebesar 0,00. Nilai
signifikansi yang didapatkan dari proses penghitungan lebih kecil daripada
p=0,05. Sehingga dari pengujian ini dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan
yang signifikan terhadap jumlah limfosit antar kelompok.
5.2.4 Uji Post Hoc Tukey HSD
Analisis mengenai perbedaan jumlah limfosit dari kesembilan kelompok
dapat diketahui dalam Post Hoc Multiple Comparison test. Metode Post Hoc
yang digunakan adalah uji Tukey HSD. Pada uji Post Hoc Tukey, sebuah data
dikatakan berbeda secara bermakna apabila nilai signifikansi p < 0.05 serta pada
interval kepercayaan 95%.
Tabel 5.5 : Uji Post Hoc Tukey HSD
K(-) 3 K(-) 5 K(-) 7 K(+) 3 K(+) 5 K(+) 7 P 3 P 5 P 7
K(-) 3 0.047* 0.901 0.212 1.000 0.010* 0.043* 0.998 0.004*
K(-) 5 0.047* 0.003* 0.000* 0.083 0.000* 0.000* 0.011* 0.000*
K(-) 7 0.901 0.003* 0.901 0.769 0.140 0.431 0.999 0.069
K(+) 3 0.212 0.000* 0.901 0.129 0.795 0.992 0.571 0.571
K(+) 5 1.000 0.083 0.769 0.129 0.005* 0.024* 0.979 0.002*
K(+) 7 0.010* 0.000* 0.140 0.795 0.005* 0.998 0.043* 1.000
P 3 0.043* 0.000* 0.431 0.992 0.024* 0.998 0.166 0.965
P 5 0.998 0.011* 0.999 0.571 0.979 0.043* 0.166 0.020*
P 7 0.004* 0.000* 0.069 0.571 0.002* 1.000 0.965 0.020*
53
Pada uji ini, suatu data dikatakan berbeda secara bermakna apabila nilai
signifikansi p<0,05 serta pada interval kepercayaan 95%. Terdapat perbedaan
yang tidak signifikan jika p=>0,05. Tabel diatas membandingkan tiap-tiap
kelompok perlakuan. Hasil uji Post Hoc Tukey menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan antara kelompok K(-)3 dengan K(-)5, K(-)3 dengan
K(+)7, K(-)3 dengan P3, K(-)3 dengan P7, K(-)5 dengan K(-)7, K(-)5 dengan
K(+)3, K(-)5 dengan K(+)7, K(-)5 denan P3, K(-)5 dengan P5, K(-)5 dengan P7,
K(+)5 dengan K(+)7, K(+)5 dengan P3, K(+)5 dengan P7, K(+)7 dengan P5, P5
dengan P7. Perbedaan yang signifikan disebabkan karena nilai (P < 0,5).
Perbedaan yang tidak signifikan ditunjukkan oleh kelompok K(-)3 dengan
K(-)7, K(-)3 dengan K(+)3, K(-)3 dengan K(+)5, K(-)3 dengan P5, K(-)5 dengan
K(+)5, K(-)7 dengan K(+)3, K(-)7 dengan K(+)5, K(-)7 dengan K(+)7, K(-)7
dengan P3, K(-)7 dengan P5, K(-)7 dengan P7, K(+)3 dengan K(+)5, K(+)3
dengan K(+)7, K(+)3 dengan P3, K(+)3 dengan P5, K(+)3 dengan P7, K(+)5
dengan P5, K(+)7 dengan P3, K(+)7 dengan P7, P3 dengan P5, P3 dengan P7.
Perbedaan yang tidak signifikan disebabkan karena nilai P > 0,05.
54
BAB VI
PEMBAHASAN
Pengamatan pada penelitian ini dilakukan di hari ke-3, ke-5 dan ke-7
setelah semua hewan coba dilakukan ulserasi. Lesi yang timbul dari trauma pada
mukosa labial tikus putih (Rattus norvegicus) menunjukkan gambaran klinis ulser
1 hari setelah induksi panas dilakukan. Tampak gambaran lesi ulser berbentuk
bulat atau oval dengan diameter ±1,5 mm, dasar lesi berwarna putih kekuningan
atau putih pucat, dikelilingi oleh pinggiran berwarna kemerahan. Hal tesebut
sesuai dengan Ghom (2014) yang menjelaskan bahwa ulkus traumatik
bentuknya tunggal dengan margin lesi kemerahan. Ukurannya sedang dan
bentuk biasanya irregular serta bisa datar atau sedikit cekung.
Pembuatan ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) dengan cara
maserasi karena metode yang digunakan sederhana tetapi efektifitasnya tinggi
untuk menarik zat-zat aktif (tanin, flavonoid) yang terkandung dalam kulit buah
delima (Punica granatum L.) (Damayanti dan Fitriana, 2012). Setelah dilakukan
proses maserasi nantinya akan didapatkan kandungan ekstrak kulit buah delima
dengan konsentrasi 100%.
Ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) diformulasikan dalam
bentuk gel karena memiliki beberapa keuntungan yaitu mudah merata jika
dioleskan tanpa penekanan, tidak membekas di kulit, memberi sensasi dingin
dan mudah digunakan (Maulina, 2015). Ekstrak kulit buah delima diformulasikan
menjadi gel dengan senyawa gelling agent sebagai bahan pembentuk gel.
Gelling agent bermacam – macam jenisnya, diantaranya adalah carboxy metil
55
selulosa (CMC), hidroxypropil methyl celulosa (HPMC), dan ada juga yang
berasal dari polimer sintetik seperti carbopol. Penelitian ini menggunakan gelling
agent carbopol yang mampu menjadi basis gel tanpa mempengaruhi zat aktif dari
kulit buah delima selain itu juga karena carbopol memiliki stabilitas dan
kompatibilitas yang tinggi dan toksisitas yang rendah (Supomo, 2016).
Dalam uji oneway ANOVA yang telah dilakukan diperoleh nilai signifikansi
sebesar 0.000 (p < 0.05) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan
jumlah limfosit yang bermakna antara kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol
positif dan kelompok perlakuan. Hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh
pemberian gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) terhadap jumlah
limfosit pada proses penyembuhan ulkus taumatik pada tikus putih (Rattus
norvegicus) yang diinduksi panas. Hal ini juga di dukung dengan penelitian yang
telah dilakukan sebelumnya oleh Cintami (2013) untuk mengukur kecepatan
penyembuhan luka bakar di kulit pada tikus putih berdasarkan jumlah sel radang,
fibroblast dan kolagen menggunakan ekstrak kulit buah delima (Punica granatum
L.) yang hasilnya lebih cepat proses penyembuhannya dibandingkan dengan
kelompok yang tidak diberi perlakuan. Penelitian lain yang dilakukan oleh
Thresianty (2013) menunjukkan bahwa aplikasi ekstrak kulit delima secara
topikal pada luka split thickness tikus putih dapat meningkatkan aktivasi limfosit
dan makrofag, meningkatkan jumlah fibroblas dan ketebalan kolagen sehingga
mempercepat proses epitelisasi dan penyembuhan luka semakin cepat.
Berdasarkan uji Post Hoc LSD (Least Significance Differences) yang
telah dilakukan sebagai lanjutan dari uji One Way ANOVA menunjukkan bahwa
pada kelompok yang tidak diberi perlakuan K(-) pada hari ke-3, ke-5 dan ke-7
mengalami peningkatan dari hari ke-3 sampai hari ke-5, dan penurunan pada
54
56
hari ke-7. Jumlah limfosit pada kelompok yang tidak diberi perlakuan K(-) dari
hari ke-3 menuju hari ke-5, sampai hari ke-7 memiliki perbedaan yang tidak
signifikan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kelompok tersebut tidak diaplikasikan
senyawa aktif yang mampu mempercepat proses penyembuhan luka, juga
menjadi tanda bahwa inflamasi masih terjadi pada kelompok tersebut. Hal ini
sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Izzaty (2014) pada kelompok
yang diberi akuades tidak memberikan perbedaan bermakna dikarenakan tidak
adanya kandungan senyawa aktif pada akuades tersebut.
Pada kelompok yang diaplikasikan Triamcinolone acetonide 0,1 % pada
hari ke-3, ke-5 dan ke-7 mengalami peningkatan dari hari ke-3 sampai hari ke-5,
dan penurunan pada hari ke-7. Pada uji Post Hoc LSD menunjukkan bahwa
peningkatan jumlah limfosit pada kelompok yang diaplikasikan Triamcinolone
acetonide 0,1 % dari hari ke-3 menuju hari ke-5, sampai ke-7 memiliki
perbedaan yang tidak signifikan. Hal ini dikarenakan karena adanya infeksi pada
daerah luka. Menurut Skidmore Roth (2014), Triamcinolone acetonide 0.1%
memiliki kontraindikasi terhadap infeksi jamur, virus, atau bakteri pada mulut dan
tenggorokan. Hal tersebut perlu diperhatikan karena penggunaan kortikosteroid
pada masa infeksi aktif dapat menekan sistem imun tubuh Pada penelitian yang
dilakukan Amtha (2017) bahwa Triamcinolone acetonide 0,1% merupakan
golongan kortikosteroid yang paling lemah untuk mencegah beberapa efek
samping seperti kandidiasis akibat pemakaian topikal yang kurang benar dan
jangka waktu yang lama. Kortikosteroid topikal dilaporkan dapat menurunkan
fungsi sel limfosit pada lokasi inflamasi sehingga menyebabkan atrofi epitel serta
menurunkan migrasi epitel dan akan menghambat penyembuhan luka.
57
Pada kelompok yang diaplikasikan gel kulit buah delima (Punica
granatum L.) pada hari ke-3, ke-5 dan ke-7 mengalami peningkatan dari hari ke-
3 sampai hari ke-5, dan penurunan pada hari ke-7. Pada uji Post Hoc LSD
menunjukkan bahwa peningkatan jumlah limfosit pada kelompok yang
diaplikasikan gel kulit buah delima (Punica granatum L.) dari hari ke-3, menuju
hari ke-5 hingga pada hari ke-7 memiliki perbedaan yang tidak signifikan. Hal
tersebut dikarenakan adanya respon jaringan terhadap stress, stress dalam
bentuk gangguan integritas seperti injury, inflamasi, respon auto-imun, dapat
menyebabkan degradasi pada protein dan senyawa fenol pada matrik
ekstraseluler seperti ellagic acid dan flavonoid. Melalui degradasi tersebut, peran
ellagic acid dan flavonoid akan hilang (Neck et al., 2012).
Pada kelompok yang diaplikasikan Triamcinolone acetonide 0,1 % K(+)
dan kelompok yang diaplikasikan gel kulit buah delima (Punica granatum L.) (P)
pada hari ke-3, ke-5 dan hari ke-7 didapatkan bahwa kelompok (P) memiliki rata-
rata jumlah limfosit yang lebih rendah dibandingkan kelompok K(+). Pada uji Post
Hoc LSD menunjukkan bahwa kelompok K(+) dengan kelompok (P) di hari ke-3,
hari ke-5 dan hari ke-7 memiliki perbedaan yang tidak signifikan. Hal ini
dikarenakan bahwa Triamcinolone acetonid 0.1% memiliki efek utama yaitu
antiinflamasi (Rebel, 2010). Begitupun pernyataan dari Laszlo (2015) yang
menyatakan bahwa kulit buah delima (Punica granatum L.) juga memiliki efek
antiinflamasi, kedua nya memiliki efek yang sama dalam mempercepat
penyembuhan luka maka dapat disimpulkan bahwa gel ekstrak kulit buah delima
(Punica granatum L.) memiliki efek yang sama dengan Triamcinolone acetonid
0.1% maka dari itu tidak ada perubahan yang signifikan dari jumlah limfosit
58
antara kelompok kontrol K(+) hari ke-3, hari ke-5, hari ke-7 dan kelompok (P) hari
ke-3, hari ke-5, dan hari ke-7.
Sedangkan pada kelompok yang tidak diberi perlakuan K(-) dan kelompok
yang diaplikasikan gel kulit buah delima (Punica granatum L.) (P) pada hari ke-3,
ke-5 dan hari ke-7 didapatkan bahwa kelompok (P) memiliki rata-rata jumlah
limfosit yang lebih rendah dibandingkan kelompok K(-). Pada uji Post Hoc LSD
menunjukkan bahwa kelompok K(-) dengan kelompok (P) di hari ke-3, hari ke-5
memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena pemberian gel
ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) pada kelompok (P). Gel ekstrak
kulit buah delima (Punica granatum L.) memiliki kandungan ellagic acid dan
flavonoid.
Flavonoid memiliki peran menghambat enzim siklooksigenase dan
lipooksigenase pada reaksi inflamasi yang mengakibatkan produksi
prostaglandin dan leukotrien berkurang. Penekanan prostaglandin sebagai
mediator inflamasi dapat menyebabkan berkurangnya nyeri dan pembengkakan,
mengurangi terjadinya vasodilatasi pembuluh darah dan aliran darah lokal,
sehingga migrasi sel radang pada area radang akan menurun. Menurunnya
jumlah leukotrien (LTB4), akan mengurangi kemotaktsis leukosit polimorfonuklear
dan adhesi PMN serta limfosit ke dinding endotel, sehingga jumlah sel PMN dan
limfosit pada area radang akan menurun. Menurunnya jumlah limfosit akan
merangsang aktivitas limfosit dalam menghasilkan limfokin interferon- ү (IFN- ү)
yaitu suatu sitokin perangsang utama untuk mengaktivasi makrofag. Limfosit
akan mengaktivasi makrofag sehingga menghasilkan faktor pertumbahan yang
berperan terhadap proses reepitelisasi, proliferasi fibroblast, dan angiogenesis.
Peningkatan reepitelisasi, proliferasi fibroblast, dan angiogenesis akan
59
mempercepat terjadinya penyembuhan luka. Ellagic acid berperan dalam
mempecepat inflamasi dengan cara menstimulasi proliferasi pembuluh darah dan
meningkatkan sintesis TGF‐β yang menstimulasi terbentuknya biosintesis
kolagen yang akan mempercepat penyembuhan luka (Pratiwi, 2011).
Pada uji Post Hoc LSD menunjukkan bahwa pada kelompok K(-) dengan
kelompok (P) hari ke-7 memiliki perbedaan yang tidak signifikan dikarenakan
bahwa pada proses penyembuhan luka jumlah limfosit yang ada akan mengalami
penurunan pada hari ke 7 (Kumar et al., 2013). Penurunan sel limfosit
menandakan bahwa proses penyembuhan telah masuk ke tahap selanjutnya
sehingga proses inflamasi terjadi lebih singkat dan penyembuhan luka menjadi
semakin cepat (Pratiwi, 2011).
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa gel
ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) berpengaruh terhadap jumlah sel
limfosit pada proses penyembuhan ulkus traumatik tikus putih (Rattus
norvegicus) yang diinduksi panas. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis
penelitian yang telah disusun dapat diterima.
55
58
60
BAB VII
PENUTUP
7.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
1. Pemberian gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) berpengaruh
terhadap jumlah sel limfosit pada proses penyembuhan ulkus traumatik tikus
putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi panas.
2. Jumlah sel limfosit yang terbentuk pada proses penyembuhan ulkus
traumatik pada kelompok yang tidak diberi perlakuan, diberi Triamcinolone
acetonide 0,1 %, dan diberi gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum
L.) hari ke-3, ke-5 dan ke-7 menunjukkan disetiap kelompok memiliki rata-
rata jumlah sel limfosit tertinggi pada hari ke-5 dan terendah pada hari ke-7.
3. Terdapat perbedaan jumlah sel limfosit pada mukosa labial tikus putih
(Rattus norvegicus) pasca diinduksi panas pada kelompok kontrol negatif,
kelompok kontrol positif dengan kelompok perlakuan
7.2. Saran
Berdasarkan kekurangan yang ada pada penelitian ini, maka perlu
diadakan penelitian yang lebih lanjut sebagai berikut:
1. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian
mengenai berbagai konsentrasi yang bervariasi terhadap gel ekstrak kulit
buah delima (Punica granatum L.) sebagai perbandingan konsentrasi yang
efektif.
61
2. Pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan pengembangan pada tingkatan
hewan coba yang lebih tinggi sehingga semakin mendekati aplikasi gel
ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L ) pada pengobatan manusia.
3. Pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan uji efek samping dan toksisitas
dari gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) sebagai terapi
penyembuhan ulkus traumatik.
61
DAFTAR PUSTAKA
Adiga S., Tomar P and Rajput R.R., 2010. Effect of Punica granatum Peel Aqueous Extract on Normal and Dexamethasone Suppressed Wound Healing in Wistar Rats. International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research vol.5, p.134–40
Al-Hajj, Methaq Algabr, Hafiz Rizwan Sharif. 2016. In Vitro and in Vivo Evaluation
of Antidiabetic Activity of Leaf Essential Oil of Pulicaria inuloides-Asteraceae. Journal of Food and Nutrition Research, vol.4, p. 461-470
Amtha, Rahmi M., M. Marcia., Anggia Irma Aninda., 2017. Plester Sariawan
Efektif Dalam Mempercepat Penyembuhan Stomatitis Aftosa Rekuren dan Ulkus Traumatikus. Majalah Kedokteran Gigi Indonesia vol.3 no.2, p. 69-75. ISNN 2442-2576(online)
Castellanos J.L., Guzman L.D., Guanajuato., 2008. Lesions of the oral mucosa: an
epidemiological study of 23785 Mexican patiens. Mosby [serial online] [cited 2017 Maret 26]; 78-85. Available from URL: http://oralpathol.dlearn.kmu.edu.tw/case/Journal%20reading-intern0803/oral%20mucosa%20lesion-epidemiological%20study-OOOE-2008.pdf
Cawson R.A., Odell E.W., 2008. Cawson’s Essential of Oral Pathology and Oral
Medicine 7 Ed. Churchill Livingstone, London, p. 261-264 Cebeci A.R.I., Gulsahi A., Kamburoglu K., Orhan B.K., Oztas B., 2009. Prevalence
and distribution of oral mucosal lesions in an adult turkish population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal [serial online] [cited 2017 Maret 28]; 14(6): 272-7. Available from URL: http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/v14i6/medoralv14i6p272.pdf
Cintami, Almahitta P. 2013. Pengaruh Ekstrak Aqueous Kulit Delima (Punica
Granatum) Peroral Terhadap Makrofag, Fibroblas Dan Kolagen Pada Penyembuhan Luka Bakar Tikus Putih. Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
Dahlan, M., 2011., Statistik Untuk Kedokteran dan Kesehatan, Salemba Medika,
Jakarta.
Damayanti, A. & E.A. Fitriana. 2012. Pemungutan Minyak Atsiri Mawar (Rose Oil) dengan Metode Maserasi. Jurnal Bahan Alam Terbarukan p. 1(2)
DeLong, L., dan Burkhart N.W., 2008. General and Oral Pathology for the Dental
Hygienist, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, p. 294-316 Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2011. Pedoman Pengendalian Tikus.
(online). http://www.depkes.go.id/downloads/Pengendalian%20Tikus.pdf (diakses 30 April 2018)
62
Ghom, A.G. dan Ghom, S.A., 2014. Textbook of Oral Medicine, Jaypee Brothers Medical Publishers ltd.: New Delhi, p. 1005
Hardjito K, WIjayanti LA, Saputri NM. 2012. Senam Kegel dan Penyembuhan Luka
Jahitan Perineum pada Ibu Post Partum. 2-TRIK: Tunas-Tunas Riset Kesehatan. Hal. 165-170.
Hardiono. 2012. Pengaruh Pemberian Ekstrak Ganggang Coklat (Phaeophyceae)
Jenis Sargassum Sp. terhadap Jumlah Limfosit pada Ulkus Traumatikus. Tesis. Tidak Diterbitkan. Fakultas Kedoktean Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya.
Hayouni, E.A., K. Miled., S. Boubaker., Bellasfar., M. Abedrabba., H.Iwaski., H.
Oku., T. Matsui., F. Limam., M.Hamdi. 2011. Hydroalcoholic Extract Based-Ointment From Punica Granatum L. Peels With Enhaced In Vivo Healing Potential on Dermal Wounds. Elsevier: Phytomedicine, vol.18, p. 976-984
Heranawati, Sri. 2015. Ekstrak Buah Delima Sebagai Terapi Recurrent Apthous
Stomatitis (RAS). Stomatognatic (J.K.G Unejj), vol.12 no.1, p. 20-25 Imuro Y. and Brenner A., 2008. Matrix Metalloproteinase Gene Delivery for Liver
Fibrosis. Pharmaceutical research, p. 25(2)
Ismail T., Sestili P., Akhtar S., 2012. Pomegranate Peel and Fruit Extracts: A Review of Potential Anti-Inflammatory and Anti-Infective Effects. Journal of Ethnopharmacology. vol. 143(2). p. 397-405
Izzaty, A., Dewi. N., Pratiwi, D. 2014. Ekstrak Haruan (Chana striata) secara
Efektif Menurunkan Jumlah Limfosit Fase Inflamasi dalam Penyembuhan Luka. Jurnal Demtofasial Vol. 13 No. 3: 176 – 181. Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Kim, J. Y., et al. 2013. Topical application of the lectin Artin M accelerates wound healing in rat oral mucosa by enhancing TGF-b and VEGF production. Wound Repair and Regeneration. p. 456-463.
Kumar V, Abbas AK, Aster JC. 2013. Inflammation and Repair. Robbins Basic Pathology 9th ed. Philadelphia: Elsevier-Saunders. p. 29-65
Laszlo, Kursinszki., 2015.Flavonoids. Semmelweis University. Department of
Pharmacognosy Madhawati, R., 2012. Si Cantik Delima (Punica granatum L.) Dengan Sejuta
Manfaat Antioksidan sebagai bahan Alternatif Alami Tampil Sehat dan Awet Muda, Universitas Negeri Malang.
Maulina, Lena., Nining Sugihartini. 2015. Formulasi Gel Ekstrak Etanol Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana L.) dengan Variasi Gelling Agent sebagai Sediaan Luka Bakar. Yogyakarta : Pharmaciana vol.5 no.1, p. 43 - 52
63
Meilawaty, Zahara., 2011. Jumlah Limfosit pada Model Inflamasi Setelah Pemberian Ekstrak Getah Biduri (Calotropis gigantea). Jember : Stomatognatic (J.K.G Unej) vol.8 no.3, p. 131 - 136
Miksusanti., 2010. Proliferasi Sel Limfosit Secara In Vitro Oleh Minyak Atsiri Temu Kunci dan Film Edibel Anti Bakteri. Journal Penelitian Sains, p. 6-7
Neck, J.V., Tuk, B., Barritault, D., Tong, M. 2012. The book Tissue Regeneration – From Basic Biology to Clinical Application, ISBN 978-953-51-0387-5. Heparan Sulfate Proteoglycan Mimetics Promote Tissue Regeneration: An Overview4: 69-92.
Neville B.W., Damm D.D., Allen C.M., et al., 2009. Oral & maxillofacial pathology. 3rd ed. Philadelphia : Saunders, p. 362-9
Permatasari, N., Robinson Pasaribu., dan Abdur Razaq K., 2012. Efektifitas
ekstrak Ginseng Asia (Panax ginseng) dalam meningkatkan jumlah pembuluh darah pada soket mandibula pasca pencabutan gigi Rattus norvegicus. Majalah FKUB. Malang.
Phillips, Jacqueline., Alison Hogan., Erin Lynch. 2013. Animal in research: Rats. Macquarie University. (online). http://theconversation.com/animals-in-research-rats-16634 (diakses tgl 29 April 2018)
Pratiwi M, 2011. Efek Ekstrak Lerak (Sapindus rarak DC) terhadap Penurunan Sel-sel Radang Pada Tikus Wistar Jantan (Penelitian In Vivo). Paper. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Available from:http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/22896. Accessed at: February 28, 2018.
Primatika A.D, Budiono U., Leksana E., 2010. Pengaruh Infiltrasi Levobupivakain Pada Skor Histologis MHC Kelas 1 Pada Penyembuhan Luka. Journal Anastesiologi Indonesia, vol.2, p. 2
Rebel Distributors Corps. 2010. Triamcinolone Acetonide Ointment USP 0.025%, 0,1%. United States of America
Regezi J.A., Sciubba J.J., Jordan R.C.K., 2012. Oral pathology clinical pathologic
correlations, 6th ed. Philadelphia: Saunders Reinke, J.M., Sorg, H. 2012. Wound Repair and Generation. Eur Surg. Res. Vol.
49(1): page 35-43.
Robbins and Kumar., 2013. Robbins Basic Pathology, 7th ed., Elsevier Saunders:
Philadelphia, p. 33-59
Savitri, E.S., 2008, Rahasia Tumbuhan Berkhasiat Obat Perspektif Islam. UIN Press, Malang.
Scully, C., 2008. Clinical Practise. Aphthous Ulceration. N Engl Journal Med
vol.355(2), p. 165-172
64
Setyarini EA, Barus LS, Dwitari A.. 2013. Perbedaan Alat Ganti Verband Antara
Dressing Set Dan Dressing Trolley Terhadap Resiko Infeksi Nosokomial Dalam Perawatan Luka Post Operasi. Jurnal Kesehatan STIKes Santo Borromeus, vol.1(1), p. 11-23
Skidmore-Roth, L., 2014., Mosby’s 2014 Nursing Drug Reference, Elsevier,
Missouri. Siebelt, Michiel., Nicoline Korthagen., Wu Wei., Harald Groen., Yvonne
Bastiaansen-Jenniskens., Christina Mullef., Jan Hendrik Waarsing., Marion de Jong., Harrie Weinans. 2015. Research Article: Triamcinolone Acetonide Activities an Anti-Inflamatory and Folate Receptor-positive Macrophage That Prevents Osteophytosis In Vivo. Arthritis Research & Therapy. Biomed Central vol.17, p. 352
Sugiaman V.K., 2011. Peningkatan Penyembuhan Luka di Mukosa Oral Melalui
Pemberian Aloe Vera (Linn.) Secara Topikal. JKM, vol.11, p. 1 Sulistiawati I.D.A.N., 2011. Pemberian Ekstrak Daun Lidah Buaya (ALOE VERA)
Konsentrasi 75% lebih Menurunkan Jumlah Makrofag daripada Konsentrasi 50% dan 25% pada Radang Mukosa Mulut Tikus Putih Jantan. Denpasar: Universitas Udayana.
Supomo, Sapri., Astri N.K., 2016. Formulasi Gel Antioksidan Ekstrak Kulit Buah
Manggis (Garcinia mangostana L.) dengan Basis Carbopol. Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin. Jurnal Ilmiah Ibnu Sina vol.1(1), p. 50-60.
Thakur M., Melzig M.F., Fuchs H., Weng A., 2011. Chemistry and pharmacology of
saponins: special focus on cytotoxic properties. P. 19-29 Thresianty, Vini.I.P., 2013. Pengaruh Pemberian Topikal Ekstrak Kulit Delima
Pada Penyembuhan Luka Split Thickness Kulit Tikus. Skripsi. Fakultas Kedoteran Universitas Airlangga
Wendy Jarrett et.al. 2015. Understanding Animal Research: Rat. (online). http://www.understandinganimalresearch.org.uk/animals/10-facts/rat/ (diakses tgl 29 April 2018)
Weston, Leslie A., Ulrike Mathesius., 2013. Flavonoids: Their Structure,
Biosynthesis and Role in the Rhizosphere, Including Allelopathy. Journal Chem Ecol vol.39, p. 283-297
Yusuf, M.S., 2014. Efektivitas penggunaan jinten hitam dalam proses percepatan
peyembuhan luka setelah pencabuatan gigi. Bagian Ilmu Bedah Mulut Universitas Hassanudin Makassar.
Zaky, Labieb Fairuz. 2017. Pengaruh Gel Campuran Lendir Bekicot (Achatina fulica) dan Ekstrak Etanol Lidah Buaya (Aloe barbadensis Miller) terhadap Jumlah Limfosit pada Proses Penyembuhan Ulkus Traumatik Mukosa