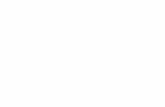Karakteristik Pektin Kulit Pisang (Musa paradisiaca) Candi ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Karakteristik Pektin Kulit Pisang (Musa paradisiaca) Candi ...
i
Karakteristik Pektin Kulit Pisang (Musa paradisiaca) Candi dari Berbagai Tingkat Kematangan yang Diekstrak dengan
Metode Maserasi Menggunakan Asam Klorida dan Asam Sitrat
SKRIPSI
Oleh:
CHESARIA MEIDINA
145100101111015
JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018
ii
Karakteristik Pektin Kulit Pisang (Musa paradisiaca) Candi dari Berbagai Tingkat Kematangan yang Diekstrak dengan
Metode Maserasi Menggunakan Asam Klorida dan Asam Sitrat
SKRIPSI
Oleh:
CHESARIA MEIDINA
145100101111015
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Teknologi Pertanian
JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018
v
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama lengkap Chesaria Meidina
dilahirkan di Denpasar pada tanggal 1 Mei 1996
merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis
lahir dari ayah yang bernama Iswanto dan Ibu yang
bernama Ni Luh Putu Indriyani. Penulis sekarang
bertempat tinggal di Perumahan BPTP Karangploso,
Kabupaten Malang.
Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di
SD N 05 Kampung Jawa, Kota Solok. Kemudian
melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Kota Solok hingga tahun 2011. Penulis
melanjutkan sekolah menengah atas di SMA N 1 Kota Solok dan lulus pada
tahun 2014. Penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi Universitas Brawijaya
Malang pada tahun 2014 sebagai mahasiswi di Jurusan Teknologi Hasil
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Selama kuliah penulis tercatat aktif
dalam berbagai kegiatan sebagai anggota divisi pendamping OPJH 2015 dan
ketua pelaksana English for Specific Purposes Orientation 2016.
vi
Alhamdulillah berkat Allah SWT karya ini mampu diselesaikan.
Karya ini kupersembahkan kepada keluargaku, terutama Bapak. Mama dan Rio.
Kakak sayang Bapak sama Mama.
vii
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Chesaria Meidina
NIM : 145100101111015
Jurusan : Teknologi Hasil Pertanian
Fakultas : Teknologi Pertanian
Judul : Karakteristik Pektin Kulit Pisang (Musa paradisiaca) Candi dari
Berbagai Tingkat Kematangan yang Diekstrak dengan Metode
Maserasi Menggunakan Asam Klorida dan Asam Sitrat
Menyatakan bahwa,
Tugas Akhir dengan judul di atas merupakan karya asli penulis tersebut diatas.
Apablia di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia
dituntut sesuai hokum yang berlaku.
Malang, 1 Oktober 2018
Pembuat Pernyataan,
Chesaria Meidina
NIM. 145100101111015
viii
CHESARIA MEIDINA . 145100101111015. Karakteristik Pektin Kulit Pisang
(Musa paradisiaca) Candi dari Berbagai Tingkat Kematangan yang
Diekstrak dengan Metode Maserasi Menggunakan Asam Klorida dan Asam
Sitrat. Tugas Akhir. Pembimbing: Prof. Dr. Teti Estiasih, STP. MP dan
Rosalina Ariesta Laeliocattleya, S.Si., M.Si
RINGKASAN
Pisang merupakan salah satu buah tropis yang banyak dihasilkan serta dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Pisang candi memiliki genom AAB dan bentuk buahnya mirip dengan pisang tanduk. Ukuran buah pisang candi lebih kecil dan jumlah sisir per tandan lebih banyak jika dibandingkan dengan pisang tanduk. Produksi pisang pada tahun 2016 mencapai 7.008 ton. Tingginya angka pemanfaatan buah pisang akan menghasilkan limbah yang besar pula. Salah satu limbah hasil pemanfaatan buah pisang adalah kulit pisang, dimana kulit pisang ini sendiri memiliki bobot sekitar 40% dari buahnya. Limbah kulit pisang yang dihasilkan hingga saat ini belum banyak dimanfaatkan, oleh karena itu jika kulit pisang diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat, maka akan memiliki nilai jual yang tinggi. Salah satu kandungan yang terdapat pada kulit pisang adalah pektin. Pektin merupakan suatu komponen serat yang terdapat pada lapisan lamella tengah dan dinding sel primer pada tanaman. Dalam industri pangan, pektin digunakan dalam pembentukan gel bahan penstabil pada sari buah, selai, jelly dan marmalade.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 3 faktor. Faktor I adalah tingkat kematangan pisang (mentah, setengah matang dan matang), faktor II adalah jenis asam (asam klorida dan asam sitrat) dan faktor III adalah konsentrasi asam (0,1 N, 0,2 N dan 0,3 N). Data yang diperoleh akan dilanjutkan dengan analisa menggunakan ANOVA (Analysis of Variance) dan dilanjutkan dengan uji DMRT dengan selang kepercayaan 95%. Tingkat kematangan pada proses ekstraksi pektin berpengaruh nyata (α = 0,05) terhadap rendemen pektin, berat ekivalen, kadar metoksil, kadar galakturonat, derajat esterifikasi dan kadar abu. Jenis asam pada proses ekstraksi pektin berpengaruh nyata (α = 0,05) terhadap rendemen pektin, berat ekivalen, kadar metoksil, kadar galakturonat, derajat esterifikasi dan kadar abu. Konsentrasi asam pada proses ekstraksi pektin berpengaruh nyata (α = 0,05) terhadap rendemen pektin, berat ekivalen, kadar metoksil, kadar galakturonat, derajat esterifikasi dan kadar abu
Kata kunci: Kulit Pisang Candi, Pektin, Ekstraksi
ix
CHESARIA MEIDINA . 145100101111015. The Characteristics of Pectin from
Banana (Musa paradisiaca) Candi Peel from Various Levels of Maturity
Extracted with Maceration Method Using Hydrochloric Acid and Citric Acid.
Undergraduate Report. Supervisor: Prof. Dr. Teti Estiasih, STP. MP and
Rosalina Ariesta Laeliocattleya, S.Si., M.Si
SUMMARY
Bananas are one of the tropical fruits that produced and utilized by the people of Indonesia. Banana (Musa paradisiaca) Candi have the AAB genome and their shapes are similar to Banana (Musa paradisiaca) Tanduk. The size of Banana (Musa paradisiaca) Candi is smaller and the number of combs per bunch is more than Banana (Musa paradisiaca) Tanduk. Banana production in 2016 reached 7,008 tons. The high rate of bananas’ used will also produce large amounts of waste. One of the wastes is banana peel, where the banana peel itself weighs about 40% of the fruit. Banana peel has not been widely used, therefore if the banana peel is processed into something useful, it will have a high selling value. One of the ingredients found in banana peel is pectin. Pectin is a component of fiber found in the middle lamella layer and primary cell wall in plants. In the food industry, pectin is used in the formation of stabilizing gels in fruit juice, jams, jelly and marmalade.
The research was conducted by using Completely Randomized Design with 3 factors. Factor I is the banana maturity level (raw, half-mature, mature), factor II is type of acid (hydrochloric acid and citric acid) and factor III is acid concentration (0,1 N, 0,2 N and 0,3 N). The data obtained was analyzed by ANOVA (Analysis of Variance) and continued by DMRT (Duncan's Multiple Range Test) with 95% confidence interval. Maturity level has influence significantly (α = 0,05) on pectin yield, ekivalen weight, metoxhyl content, galacturonit content, degree of esterification and ash content. Type of acid has influence significantly (α = 0,05) on pectin yield, ekivalen weight, metoxhyl content, galacturonit content, degree of esterification and ash content. Acid concentration has influence significantly (α = 0,05) on pectin yield, ekivalen weight, metoxhyl content, galacturonit content, degree of esterification and ash content.
Keyword : Banana (Musa paradisiaca) Candi Peel, Pectin, Extraction
x
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat
dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul Karakteristik Pektin Kulit
Pisang (Musa paradisiaca) Candi dari Berbagai Tingkat Kematangan yang
Diekstrak dengan Metode Maserasi Menggunakan Asam Klorida dan Asam Sitrat
dapat diselesaikan. Tersusunnya naskah ini, tidak lepas dari bantuan dari
beberapa pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan
terima kasih kepada :
1. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan baik
dari segi mental dan materi kepada penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Teti Estiasih, STP. MP dan Ibu Rosalina Ariesta
Laeliocattleya, S.Si., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah
membimbing dan memberi masukan selama proses penyusunan dan
penyelesaian tugas akhir ini.
3. Civitas akademik Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya.
4. Teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan semangat
kepada penulis. Terutama Meds (Dzur, Cil, Inyan, Tir, Bebgi, Beta).
5. Lieb yang telah mendampingi penulis selama ini dalam senang maupun
susah walaupun kita LDR-an. Eheh
Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
Malang, Oktober 2018
Penulis,
Chesaria Meidina
xi
DAFTAR ISI
COVER ................................................................................................................. i LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................................. iii LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................. iv RIWAYAT HIDUP ................................................................................................ v PERUNTUKAN................................................................................................... vi PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR ..................................................... vii RINGKASAN .................................................................................................... viii KATA PENGANTAR ........................................................................................... x DAFTAR ISI ....................................................................................................... xi DAFTAR TABEL .............................................................................................. xiii DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiv DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xv
I. PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................ 3 1.3 Tujuan ........................................................................................................... 3 1.4 Manfaat ......................................................................................................... 3 1.5 Hipotesis ....................................................................................................... 3
II. TINJAUAN PUSTAKA................................................................................... 4
2.1 Pisang ........................................................................................................... 4 2.1.1 Pisang Candi ......................................................................................... 5 2.1.2 Kulit Pisang .......................................................................................... 6
2.2 Pektin............................................................................................................ 7 2.2.1 Pengertian Pektin .................................................................................. 7 2.2.2 Sifat Pektin ............................................................................................ 9 2.2.3 Kegunaan Pektin ................................................................................. 10 2.2.4 Ekstraksi ............................................................................................ 11 2.2.5 Karakterisasi Pektin ............................................................................ 14
2.3 Jenis Asam .................................................................................................. 18 2.3.1 Asam Klorida ....................................................................................... 18 2.3.2 Asam Sitrat ......................................................................................... 19
III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN ........................................................ 20
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan ................................................................. 20 3.2 Alat dan Bahan Penelitian ............................................................................ 20
3.2.1 Alat...................................................................................................... 20 3.2.2 Bahan ................................................................................................. 20
3.3 Metode Penelitian ........................................................................................ 20 3.4 Pelaksanaan Penelitian................................................................................ 22
3.4.1 Pembuatan Tepung Kulit Pisang ......................................................... 22 3.4.2 Ekstraksi Pektin................................................................................... 22 3.4.3 Analisa ................................................................................................ 23
3.5 Analisa Data ................................................................................................ 24 3.6 Diagram Alir ................................................................................................. 25 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN....................................................................... 27
4.1 Karakteristik Bahan Baku ............................................................................. 27
xii
4.2 Karakteristik Pektin Kulit Pisang Candi ........................................................ 27 4.2.1 Rendemen Pektin ................................................................................ 27 4.2.2 Berat Ekivalen ...................................................................................... 31 4.2.3 Kadar Metoksil ..................................................................................... 34 4.2.4 Kadar Galakturonat .............................................................................. 37 4.2.5 Derajat Esterifikasi ............................................................................... 41 4.2.6 Kadar Air .............................................................................................. 44 4.2.7 Kadar Abu ............................................................................................ 46 V. KESIMPULAN DAN SARAN........................................................................ 51
5.1 Kesimpulan .................................................................................................. 51 5.2 Saran ........................................................................................................... 51 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 52 LAMPIRAN ........................................................................................................ 59
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Kandungan dalam kulit pisang per 100 gram ....................................... 6
Tabel 2.2 Standar mutu pektin ....................................................................... …14
Tabel 2.3 Karakteristik Pektin Kulit Pisang Uli ............................................... …18
Tabel 2.4 Karakteristik Pektin Kulit Pisang Saba ........................................... …19
Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan Rancangan Percobaan .................................... 21
Tabel 4.1 Karakteristik Kulit Pisang Candi Segar ............................................... 27
Tabel 4.2 Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi Asam
terhadap Rendemen Pektin Kulit Pisang Candi.................................................. 28
Tabel 4.3 Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi Asam
terhadap Berat Ekivalen Pektin Kulit Pisang Candi ............................................ 32
Tabel 4.4 Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi Asam
terhadap Kadar Metoksil Pektin Kulit Pisang Candi ........................................... 35
Tabel 4.5 Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi Asam
terhadap Kadar Galakturonat Pektin Kulit Pisang Candi .................................... 38
Tabel 4.6 Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi Asam
terhadap Derajat Esterifikasi Pektin Kulit Pisang Candi ..................................... 42
Tabel 4.7 Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi Asam
terhadap Kadar Air Pektin Kulit Pisang Candi .................................................... 45
Tabel 4.8 Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi Asam
terhadap Berat Ekivalen Pektin Kulit Pisang Candi ............................................ 47
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Tingkat kematangan pisang ............................................................. 5
Gambar 2.2 Pisang candi .................................................................................... 5
Gambar 2.3 Struktur molekul asam pektinat ............................................................ 8
Gambar 2.4 Struktur molekul asam pektat .......................................................... 8
Gambar 2.5 Skema perubahan protopektin ............................................................. 8
Gambar 2.6 Struktur pektin ................................................................................. 9
Gambar 2.7 Struktur pektin bermetoksil tinggi........................................................ 10
Gambar 2.8 Struktur pektin bermetoksil rendah ..................................................... 10
Gambar 2.9 Struktur asam sitrat ....................................................................... 19
Gambar 3.1 Diagram alir persiapan bahan ........................................................ 25
Gambar 3.2 Diagram alir ekstraksi pektin .......................................................... 26
Gambar 4.1 Grafik Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi
Asam terhadap Rendemen Pektin Kulit Pisang Candi........................................ 29 Gambar 4.2 Grafik Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi
Asam terhadap Berat Ekivalen Kulit Pisang Candi ............................................. 33 Gambar 4.3 Grafik Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi
Asam terhadap Kadar Metoksil Pektin Kulit Pisang Candi.................................. 36 Gambar 4.4 Grafik Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi
Asam terhadap Kadar Galakturonat Pektin Kulit Pisang Candi .......................... 39 Gambar 4.5 Grafik Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi
Asam terhadap Derajat Esterifikasi Pektin Kulit Pisang Candi ........................... 43 Gambar 4.6 Grafik Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi Asam terhadap Kadar Air Pektin Kulit Pisang Candi .......................................... 46 Gambar 4.7 Grafik Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi Asam terhadap Derajat Esterifikasi Pektin Kulit Pisang Candi ........................... 48
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Prosedur Analisa ............................................................................ 60
Lampiran 2 Color Chart Pisang……………..………………………………………64
Lampiran 3 Hasil Analisa Rendemen Pektin ………………………………………65
Lampiran 4 Analisa Keragaman Rendemen Pektin ........................................... 66
Lampiran 5 Uji Lanjut DMRT 5% Interaksi Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan
Konsentrasi Asam terhadap Rendemen Pektin .................................................. 67
Lampiran 6 Hasil Analisa Berat Ekivalen .......................................................... 68
Lampiran 7 Analisa Keragaman Berat Ekivalen ................................................ 69
Lampiran 8 Uji Lanjut DMRT 5% Interaksi Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan
Konsentrasi Asam terhadap Berat Ekivalen ....................................................... 70
Lampiran 9 Hasil Analisa Kadar Metoksil .......................................................... 71
Lampiran 10 Analisa Keragaman Kadar Metoksil ............................................. 72
Lampiran 11 Uji Lanjut DMRT 5% Interaksi Tingkat Kematangan, Jenis Asam
dan Konsentrasi Asam terhadap Kadar Metoksil................................................ 73
Lampiran 12 Hasil Analisa Kadar Galakturonat................................................. 74
Lampiran 13 Analisa Keragaman Kadar Galakturonat ...................................... 75
Lampiran 14 Uji Lanjut DMRT 5% Interaksi Tingkat Kematangan, Jenis Asam
dan Konsentrasi Asam terhadap Kadar Galakturonat ........................................ 76
Lampiran 15 Hasil Analisa Derajat Esterifikasi .................................................. 77
Lampiran 16 Keragaman Derajat Esterifikasi ................................................... 78
Lampiran 17 Uji Lanjut DMRT 5% Interaksi Tingkat Kematangan, Jenis Asam
dan Konsentrasi Asam terhadap Derajat Esterifikasi.......................................... 79
Lampiran 18 Hasil Analisa Kadar Air ................................................................ 80
Lampiran 19 Analisa Keragaman Kadar Air ...................................................... 81
Lampiran 20 Uji Lanjut DMRT 5% Interaksi Tingkat Kematangan, Jenis Asam
dan Konsentrasi Asam terhadap Kadar Air ....................................................... 82
Lampiran 21 Hasil Analisa Kadar Abu .............................................................. 83
Lampiran 22 Analisa Keragaman Kadar Abu .................................................... 84
Lampiran 23 Uji Lanjut DMRT 5% Interaksi Tingkat Kematangan, Jenis Asam
dan Konsentrasi Asam terhadap Kadar Abu ...................................................... 85
Lampiran 24 Dokumentasi Selama Penelitian................................................... 86
1
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pisang atau buah yang memiliki nama latin Musa paradisiaca adalah
salah satu buah tropis yang banyak dihasilkan serta dimanfaatkan oleh
masyarakat Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik produksi pisang mencapai
7.008 ton pada tahun 2016. Pemanfaatan buah pisang dalam jumlah besar akan
menghasilkan limbah berupa kulit pisang yang besar pula, dimana kulit pisang ini
sendiri memiliki bobot sekitar 40% dari buahnya (Tchobanoglous, 2003).
Umumnya, kulit pisang yang dihasilkan belum banyak dimanfaatkan.
Biasanya kulit pisang dijadikan sebagai makanan ternak ataupun dibuang
sebagai limbah organik. Oleh karena itu jika kulit pisang diolah menjadi sesuatu
yang bermanfaat, maka akan memiliki nilai jual yang tinggi. Salah satu
kandungan yang terdapat pada kulit pisang adalah pektin. Kandungan pektin
yang terdapat di dalam kulit pisang bervariasi tergantung jenis atau varietasnya.
Biasanya kandungan pektin bervariasi sekitar 1,92 hingga 3,25% dari berat
kering (Hutagalung, 2013). Fitria (2013) menyebutkan bahwa kulit pisang kepok
mengandung senyawa pektin sebanyak 10,78%. Sedangkan menurut Castillo
(2015), kulit pisang saba mengandung pektin sekitar 17,05%.
Pektin merupakan suatu komponen serat yang terdapat pada lapisan
lamella tengah dan dinding sel primer pada tanaman (Sirotek, et.al, 2004). Pektin
berfungsi sebagai bahan perekat antara dinding sel yang satu dengan yang
lainnya, oleh karena itu jika seseorang mengupas buah maka akan terasa sifat
“lekat”. Pektin tersusun dari substansi seperti asam poligalakturonat, dimana
gugus karboksil dari unit asam poligalakturonat dapat teresterifikasi sebagian
dengan methanol (Habullah, 2001).
Penggunaan pektin sudah dilakukan baik pada industri pangan,
kesehatan dan juga pada industri karet. Untuk mencukupi kebutuhan pektin
dalam negeri, saat ini Indonesia masih mengimpor pektin. Indonesia merupakan
negara pengimpor dan pemakai pektin yang cukup besar karena banyaknya
industri di Indonesia yang menggunakan pektin, mulai dari industri makanan dan
minuman hingga industri tekstil (Sulihono, 2012). Menurut Badan Pusat Statistik,
jumlah impor pektin di Indonesia dari tahun 2008-2012 secara berurutan yaitu
147,6 ton; 147,3 ton; 291,9 ton; dan 240,8 ton (Hanum, 2012). Oleh karena itu
2
perlu adanya usaha untuk menghasilkan pektin untuk dapat mengurangi jumlah
pektin yang diimpor sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa
besar kandungan pektin yang ada di dalam kulit pisang candi dan bagaimana
karakteristiknya.
Kandungan pektin pada tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor
seperti tingkat kematangan buah, jenis pelarut serta konsentrasi pelarut. Larutan
pengekstrak yang dapat digunakan dalam proses ekstraksi pektin adalah air,
alkohol, larutan asam, dan polifosfat. Larutan asam yang umum digunakan
adalah HCl, H2SO4, dan CH3COOH. Larutan asam lain yang dapat digunakan
adalah asam sitrat, asam laktat, dan asam tartrat (Fellows, 2002). Menurut
Tuhuloula (2013) dan Subagyo (2010) hasil terbaik perlakuan didapatkan dari
ekstraksi menggunakan asama klorida (HCl). Sedangkan menurut Febriyanti
(2018) dan Susilowati (2013) hasil terbaik perlakuan didapatkan dari ekstraksi
menggunakan asama sitrat, Ekstraksi pektin dengan menggunakan pelarut asam
merupakan cara ekstraksi yang umum digunakan karena kemungkinan terjadi
kerusakan pektin lebih sedikit. Pada proses ekstraksi, pemilihan jenis pelarut dan
konsentrasi pelarut perlu diperhatikan. Susanti (2015) mengatakan bahwa
semakin besar normalitas larutan maka semakin besar pula rendemen yang
dihasilkan. Konsentrasi serta jumlah pelarut akan berpengaruh terhadap efisiensi
ekstraksi dan dalam jumlah tertentu pelarut dapat bekerja secara optimal, namun
jumlah yang berlebihan tidak akan mengekstrak lebih banyak (Susanto, 1999).
Jenis asam yang berbeda akan berhubungan dengan tingkat hidrolisis yang
berbeda. Hal itu disebabkan karena kekuatan asam yang berbeda akan
menghasilkan karakteristik pektin yang berbeda pula (Garna, 2007).
Kandungan dan karakteristik pektin kulit pisang candi pada berbagai
tingkat kematangan belum diketahui, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang
ekstraksi dan karakterisasi pektin dari kulit pisang candi dengan tingkat
kematangan yang berbeda.
3
1.2 Rumusan masalah
1.2.1 Bagaimana pengaruh tingkat kematangan yang berbeda yaitu mentah,
setengah matang dan matang terhadap karakteristik pektin kulit pisang
candi?
1.2.2 Bagaimana pengaruh jenis asam yang berbeda yaitu asam klorida dan
asam sitrat terhadap karakteristik pektin kulit pisang candi?
1.2.3 Bagaimana pengaruh konsentrasi asam yang berbeda 0,1 N, 0,2 N dan
0,3 N terhadap karakteristik pektin kulit pisang candi?
1.3 Tujuan penelitian
1.3.1 Mengetahui karakteristik pektin hasil ekstraksi dari kulit pisang candi
dengan variasi tingkat kematangan pisang yang berbeda yakni mentah,
setengah matang dan matang.
1.3.2 Mengetahui karakteristik pektin hasil ekstraksi dari kulit pisang candi
dengan variasi asam yang berbeda yaitu asam klorida dan asam sitrat.
1.3.3 Mengetahui karakteristik pektin hasil ekstraksi dengan dari kulit pisang
candi dengan variasi konsentrasi pelarut yang berbeda yaitu 0,1 N, 0,2 N
dan 0,3 N.
1.4 Manfaat Hasil Penelitian
Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan
informasi karakteristik pektin hasil ekstraksi dari kulit pisang candi dengan variasi
tingkat kematangan pisang yang berbeda yakni mentah, setengah matang dan
matang menggunakan variasi asam klorida dan asam sitrat dengan variasi
konsentrasi 0,1 N, 0,2 N dan 0,3 N.
1.5 Hipotesis
Tingkat kematangan pisang candi, serta jenis dan konsentrasi asam
yang berbeda diduga akan mempengaruhi karakteristik pektin dari kulit pisang
candi yang dihasilkan.
4
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pisang
Pisang merupakan buah yang tumbuh di daerah tropis. Menurut Badan
Pusat Statistik produksi pisang mencapai 7.008 ton pada tahun 2016. Tanaman
pisang bisa dikatakan sebagai tanaman serbaguna, mulai dari akar, batang
(bonggol), batang semu (pelepah), daun, bunga, buah hingga kulitnya pun dapat
dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Adapun taksonomi tanaman pisang
menurut USDA (2017) diklasifikasikan sebagai berikut :
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Superdivisi : Spermatophyta
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Liliopsida
Subkelas : Zingiberidae
Order : Zingiberales
Family : Musaceae
Genus : Musa L.
Spesies : Musa paradisiaca L.
Pada musim kemarau, pisang biasanya sudah bisa dipanen 80 hari
sejak keluarnya jantung. Sedangkan pada musim hujan, pisang bisa dipanen
setelah 120 hari. Ciri-ciri pisang yang sudah bisa dipanen antara lain kulit buah
menjadi lebih cerah, bentuk buah lebih membulat tidak bersiku. Tingkat
kematangan dibagi dalam beberapa tingkat. Tingkat pertama, berwarna hijau.
Selanjutnya, warna hijau tetapi sudah ada bintik kuning. Ketiga, warna kuning
sudah banyak, tetapi hijau masih dominan. Kemudian warna kuning lebih
dominan, sudah merata, dengan sedikit hijau di ujungnya. Pisang sudah
mencapai kematangan optimum ketika seluruh kulitnya berwarna kuning. Proses
sudah selesai dan memasuki pembusukan ketika bercak cokelat muncul.
Terakhir, bila bintik cokelat sudah merata, berarti pisang mulai membusuk
(Prabawati, 2008). Berikut adalah tingkat kematangan pisang berdasarkan
warnanya :
5
2.1.1 Pisang Candi
Pisang candi merupakan salah satu komoditas yang banyak dihasilkan di
daerah Malang, khususnya di desa Kaumrejo. Luas lahan pisang di dusun
tersebut kurang lebih mencapai 20 hektar dengan hasil perharinya kurang lebih
sebanyak 5 ton. Pisang-pisang ini kebanyakan tidak diolah oleh masyarakat dan
langsung dijual mentah kepada pengepul dengan harga rata-rata Rp. 25.000,00
pertandon (Sunandar, 2017). Pisang candi merupakan pisang yang memiliki
genom AAB. Bentuk buah pisang candi ini mirip dengan pisang tanduk. Namun
ukuran buah pisang candi lebih kecil dan jumlah sisir per tandan lebih banyak
jika dibandingkan dengan pisang tanduk. Pisang candi biasanya memiliki 5 sisir
per tandan dengan jumlah buah per sisir kurang lebih 12 buah. Umumnya pisang
candi memiliki panjang sekitar 16-20cm dan memiliki bentuk ujung buah yaitu
runcing memanjang. Pisang candi yang sudah matang akan memiliki warna kulit
dan daging kuning, serta tidak memilliki biji (Sutanto, 2005).
Gambar 2.2 Pisang Candi
Sumber : (Sutanto, 2005)
Gambar 2.1 Tingkat Kematangan Pisang
Sumber : (Aurore, 2009)
Sangat
hijau
2
Lebih hijau
dengan
sedikit kuning
3
Lebih kuning
dengan
sedikit hijau
4
Kuning dengan
ujung berwarna
hijau
5
Sangat
kuning
6
Keseluruhan
kuning dengan
bintik-bintik coklat
7
6
Tingkat ketuaan buah merupakan faktor penting pada mutu buah pisang.
Buah yang dipanen kurang tua, meskipun bisa matang namun kualitasnya akan
kurang baik karena rasa dan aromanya tidak berkembang baik. Namun, bila
dipanen terlalu tua maka rasa manis dan aroma buah kuat tetapi memiliki masa
segar yang pendek. Oleh karena itu tingkat ketuaan pada saat dipanenen sangat
berkaitan dengan jangkauan pemasaran dan tujuan penggunaan buah. Untuk
tingkat kemerahan (*a) semakin tinggi nilainya menuju negatif maka menyatakan
produk semakin hijau, sedangkan semakin positif nilai a* berarti warna produk
semakin merah (Prabawati dkk, 2008).
2.1.2 Kulit pisang
Kulit pisang merupakan limbah (bahan buangan) yang jumlahnya kira-kira
1/3 dari buah pisang yang belum dikupas. Pada umumnya, kulit pisang belum
dimanfaatkan secara maksimal dan hanya dibuang sebagai limbah organik
ataupun dijadikan pakan hewan ternak. Padahal kandungan gizi yang terdapat
pada kulit pisang terbilang cukup lengkap, seperti karbohidrat, protein, lemak,
fosfor, kalsium, vitamin B, vitamin C, zat besi dan air (Munadjim, 1988). Kulit
pisang juga mengandung pigmen karotenoid yang merupakan kelompok pigmen
yang berwarna kuning, oranye, merah oranye, serta larut dalam minyak (lipida)
(Suparmi, 2013). Berikut merupakan kandungan yang terkandung dalam kulit
pisang dapat dilihat pada Tabel 2.1,
Tabel 2.1 Kandungan yang Terkandung dalam Kulit Pisang Kepok Per 100 Gram
No. Zat Gizi Kadar
1 Air (g) 68,90
2 Karbohidrat (g) 18,50
3 Lemak (g) 2,11
4 Protein (g) 0,32
5 Kalsium (mg) 715
6 Fosfor (mg) 117
7 Zat besi (mg) 1,60
8 Vitamin B (mg) 0,12
9 Vitamin C (mg) 17,50
Sumber : Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, Jatim, Surabaya (1982).
7
2.2 Pektin
2.2.1 Pengertian Pektin
Pektin merupakan suatu komponen serat yang terdapat pada lapisan
lamella tengah dan dinding sel primer pada tanaman serta membentuk sekitar
40% (berat kering) dari dinding sel buah dan sayuran (Sirotek, et.al, 2004).
Pektin memiliki bobot molekul tinggi dan merupakan komponen penting dalam
pertumbuhan sel awal serta dalam proses pematangan (Abid, 2016). Bobot
molekul pektin bervariasi antara 30.000-300.000 (Hastuti, 2016). Pektin berfungsi
sebagai bahan perekat antara dinding sel yang satu dengan yang lainnya, oleh
karena itu jika seseorang mengupas buah maka akan terasa sifat “lekat”. Pektin
tersusun dari substansi seperti asam poligalakturonat, dimana gugus karboksil
dari unit asam poligalakturonat dapat teresterifikasi sebagian dengan metanol
(Hasbullah, 2001).
Struktur senyawa pektin merupakan polimer asam D-galakturonat yang
dihubungkan dengan ikatan β-(1,4)-glukosida. Asam D-galakturonat memiliki
struktur yang sama seperti struktur D-galaktosa, dimana perbedannya terletak
pada gugus alkohol primer C6 yang memiliki gugus karboksilat (Hart, 2003).
Polisakarida ini mengandung 300-1000 unit asam galakturonat.
Pektin bisa digunakan sebagai agen pembentuk gel dan pengental, agen
pengemulsi dan juga bisa digunakan sebagai stabilizer pada industri makanan
(Rao and Silva, 2006).
Terdapat beberapa bentuk senyawa pektin, antara lain :
a. Protopektin merupakan substansi pektin yang tidak larut dalam air,
banyak terdapat pada jaringan tanaman yang muda. Jika jaringan ini
dihidrolisis dalam air yang juga mengandung asam maka protopektin
akan berubah menjadi pektin yang mudah terdispersi dalam air
(Winarno, 2004).
b. Asam pektinat merupakan asam poligalakturonat yang memiliki sifat
koloid serta di dalam molekulnya terdapat metil ester pada beberapa
gugus karboksil sepanjang rantai polimernya. Pektin adalah asam
pektinat yang memiliki kandungan metil ester dan derajat netralisasi yang
berbeda-beda (Hanum, 2012). Berikut adalah struktur molekul senyawa
pektin :
8
c. Asam pektat merupakan senyawa asam galakturonat yang bersifat koloid
dan pada dasarnya bebas dari kandungan metil ester. Asam pektat
dapat membantuk garam seperti asam-asam lain dan terdapat pada
jaringan tanaman sebagai kalsium atau magnesium pektat (Maulana,
2015).
Berikut adalah skema perubahan protopektin :
Meskipun pektin banyak ditemukan pada jaringan tanaman, namun
sumber yang dapat digunakan untuk pembuatan pektin komersial sangat
terbatas. Hal tersebut dikarenakan kemampuan pektin untuk membentuk gel
tergantung pada ukuran molekul dan derajat esterifikasi (DE). Pektin yang
berasal dari sumber yang berbeda akan menghasilkan derajat esterifikasi yang
Gambar 2.5 Skema perubahan protopektin
menjadi pektin dan asam pektat
Sumber : (Nurhikmat, 2003)
Gambar 2.3 Struktur molekul asam pektinat
Sumber : (Sulihono, 2012)
Gambar 2.4 Struktur molekul asam pektat
Sumber : (Sulihono, 2012)
9
berbeda pula. Oleh karena itu jumlah rendemen pektin dalam bahan saja tidak
memenuhi syarat bahan sebagai sumber pektin komersial (Hastuti, 2016).
Pektin komersial bisa didapatkan dari berbagai sumber, dimana biasanya
didapatkan dari kulit apel dan kulit jeruk (Maran et al, 2013). Sedangkan sumber
lain yang menghasilkan pektin adalah produk hasil pertanian seperti sekam biji
kakao, persik, kulit pisang, kepala bunga matahari, kulit durian, kulit buah delima
dan kulit buah papaya (Raji et al, 2016)
2.2.2 Sifat Pektin
Sifat-sifat pektin ditentukan oleh struktur molekul pektin. Menurut Muhidin
(2001), sifat fisik dari pektin adalah berbentuk serbuk berwarna putih kekuningan
yang tidak larut dalam pelarut organik, akan tetapi larut dalam air panas pada
suasana asam dan juga akan membentuk gel jika ditambah air dan gula dalam
keadaan asam. Makin tinggi kadar metoksil yang dikandung dalam suatu pektin
maka makin cepat pektin berubah menjadi gel.
Sedangkan untuk sifat kimia dari pektin bersifat asam dan koloidnya
bermuatan negatif karena adanya gugus karboksil bebas (Nelson, 1997). Pektin
merupakan senyawa hidrokarbon yang berat molekulnya besar yang di dalamnya
terdapat sisa-sisa asam galakturonat disambung oleh atom atom oksigen
menjadi sebuah rantai. Di samping gugus karboksil dalam rantai ini terdapat juga
gugus COOCH3 (gugus metoksil) (Fitria, 2013). Berikut merupakan gambar
struktur dari pektin :
Berdasarkan jumlah kandungan metoksil, pektin terbagi 2 yaitu :
a. Pektin bermetoksil tinggi (High Methoxyl Pectin)
Memiliki kandungan metoksil lebih dari 7,12%. Bersifat larut dalam air dingin,
mampu membentuk gel dengan adanya penambahan gula dan asam dalam
perbandingan tertentu (Hariyati, 2006).
Gambar 2.6 Struktur pektin
Sumber : (Hastuti, 2016)
10
Mekanisme pembentukan gel pada pektin bermetoksil tinggi (HMP) adalah
rantai pektin yang dihidrasi dengan cara mengganti molekul air oleh molekul
terlarut akan menyebabkan terjadi kontak yang lebih luas antara rantai-rantai
pektin yang menghasilkan jaringan kompleks molekul polisakarida. Sebagian dari
molekul ini berikatan melalui ikatan hidrogen. Disela-sela jaringan ini molekul air
dan molekul terlarut terperangkap. Pektin bermetoksil tinggi umumnya digunakan
dalam industri jus atau sari buah, selai, susu, jeli, buah kalengan dan gula-gula
(Hastuti, 2016).
b. Pektin bermetoksil rendah (Low Methoxyl Pectin)
Memiliki kandungan metoksil 2,5-7,12% dan bersifat larut dalam alkali.
Mampu membentuk gel tanpa adanya penambahan gula tetapi perlu adanya ion
divalen, misalnya ion kalsium (Hariyati, 2006).
Mekanisme yang terjadi adalah hubungan antara molekul-molekul pektin
yang berdekatan oleh kation divalent membentuk struktur tiga dimensi melalui
pembentukan garam dengan gugus karboksil dari pektin (Fitriani, 2003). Pektin
bermetoksil rendah sensitif terhadap kation bivalen sehingga bisa diaplikasikan
sebagai adsorben logam berat (Hastuti, 2016).
2.2.3 Kegunaan Pektin
Pektin digunakan di industri makanan dan minuman sebagai agen
pengental, pembentuk gel dan zat penstabil koloid (Hastuti, 2016). Pada bidang
farmasi pektin biasanya digunakan sebagai campuran obat-obatan untuk
berbagai jenis penyakit seperti obat diare, obat luka, disentri radang usus besar,
pengganti plasma darah dan pektin juga digunakan untuk memperlambat
Gambar 2.7 Struktur pektin bermetoksil tinggi
Sumber : (IPPA, 2002)
Gambar 2.8 Struktur pektin bermetoksil rendah
Sumber : (IPPA, 2002)
11
absorbsi beberapa jenis obat-obatan tertentu di dalam tubuh sehingga dapat
memperpanjang masa kerja suatu obat.
Pada bidang kecantikan biasanya pektin digunakan untuk campuran
berbagai jenis kosmetik seperti pada pembuatan cream dan handbody lotion,
sabun, pasta gigi serta minyak rambut (Nurviani, 2014). Selain dalam bidang
diatas, pektin bisa digunakan untuk pembuatan resin sintesis dan perekat,
sebagai stabilisator pada pembuatan koloid logam serta sebagai bahan baku
peledak dalam bentuk nitro pektin, asetil pektin dan formil pektin. Pektin juga
memiliki beberapa sifat unik yang memungkinkannya digunakan sebagai matriks
penyerap logam di bidang lingkungan hidup. Pektin pun bisa digunakan pada
industri tekstil dan industri karet (Muhidin, 1999).
2.2.4 Ekstraksi
Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan
menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika
tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut
dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut
dipisahkan dari sampel dengan penyaringan (Mukhriani, 2014). Berikut
adalah beberapa metode ekstraksi yang biasa digunakan :
a. Maserasi
Maserasi merupakan cara sederhana yang biasanya dilakukan
dengan cara merendam serbuk yang akan diekstrak didalam larutan
pengekstrak. Larutan pengekstrak nantinya akan menembus dinding sel
dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif
yang terdapat dalam serbuk ini nantinya akan larut dan larutan yang
terpekat didesak keluar dikarenakan adanya perbedaan konsentrasi
antara larutan zat aktif di dalam sel dengan di luar sel. Peristiwa tersebut
terjadi secara berulang sehingga akan terjadilah keseimbangan
konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel (Pratiwi, 2010).
Proses perendaman ini bisa dilakukan tanpa pemanasan (pada
temperatur kamar), dengan pemanasan atau bahkan pada suhu
pendidihan. Larutan pengekstrak yang biasa digunakan dapat berupa air,
etanol, air-etanol atau pelarut lainnya (Harmita, 2008). Keuntungan dari
maserasi adalah cara pengerjaannya sederhana dan peralatan yang
digunakan mudah ditemukan (Agoes, 2007).
12
b. Perkolasi
Perkolasi dilakukan dengan cara membasahi serbuk yang akan
diekstrak dan dialiri dengan larutan pengekstrak menggunakan
perkolator. Perkolator adalah alat yang digunakan untuk mengekstrak
terbuat dari bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori.
Larutan pengekstrak akan melarutkan zat aktif dari sel-sel yang dilalui
hingga mencapai keaadan jenuh kemudian dibiarkan menetes (Ansel,
1989). Keuntungan dari metode perkolasi adalah tidak memerlukan
pemanasan sehingga metode ini tepat digunakan untuk substansi yang
tidak tahan terhadap panas dan juga penarikan zat aktif dari serbuk yang
akan diekstrak lebih sempurna (Agoes, 2007).
c. Sokletasi
Sokletasi merupakan metode ekstraksi yang menggunakan
pelarut yang selalu barudan umumnya dilarutkan dengan alat khusus
sehingga terjadi ekstraksi kontinyu dengan jumlah pelarut yang relatif
konstan dengan adanya pendingin balik. Sampel akan dibalut oleh kertas
saring dan ditempatkan di dalam soklet. Alat soklet kemudian akan
mengosongkan isinya ke dalam labu dasar bulat setelah pelarut
mencapai kadar tertentu. Setelah pelarut segar melewati alat ini melalui
pendingin refluks, ekstraksi berlangsung sangat efisien dan senyawa dari
bioasa secara efektif ditarik ke dalam pelarut karena konsentrasi awalnya
rendah dalam pelarut (Istiqomah, 2013). Keuntungan dari menggunakan
metode sokletasi ini adalah ekstrak yang dihasilkan lebih banyak, pelarut
yang digunakan lebih sedikit, waktu yang digunakan lebih cepat, dan
sampel diekstraksi secara sempurna karena dilakukan berulang-ulang
(Puspitasari, 2016).
d. Refluks
Refluks merupakan metode ekstraksi dengan pelarut pada
temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut
terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya
dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali
sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna (Depkes RI, 2000).
Biasanya metode ini digunakan jika pelarut yang digunakan bersifat
volatile (mudah menguap). Prinsip dari metode refluks adalah pelarut
volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan
13
didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam
bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam
wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi
berlangsung. Keuntungan dari metode ini antara lain bisa digunakan
untuk mengekstraksi sampel-sampel yang mempunyai tekstur kasar dan
sampel-sampel yang tahan pemanasan secara langsung (Agoes, 2007).
2.2.4.1 Ekstraksi Pektin
Pemisahan pektin dari jaringan tanaman asalnya bisa dilakukan dengan
cara ekstraksi. Proses ekstraksi pektin terdiri dari 4 tahap yaitu ekstraksi,
pengendapan, pencucian serta pengeringan (Nurviani, 2014). Ekstraksi adalah
suatu proses pemisahan dari bahan padat maupun bahan cair dengan bantuan
pelarut. Pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang
diinginkan tanpa melarutkan material lain. Ekstraksi menggunakan pelarut
didasarkan pada kelarutan komponen lain dalam campuran (Tuhuloula, 2013).
Beberapa jenis pelarut yang dapat melarutkan pektin adalah air, beberapa
senyawa organik, senyawa alkalis dan asam. Dalam proses ekstraksi pektin
terjadi perubahan senyawa pektin yang diakibatkan oleh proses hidrolisis
protopektin. Adanya pemanasan dalam asam pada suhu dan lama waktu
ekstraksi akan menyebabkan protopektin berubah menjadi pektinat (pektin). Jika
proses hidrolisis tersebut dilanjutkan maka senyawa pektin tersebut akan
berubah menjadi asam pektat (Nurhikmat, 2003).
Pengendapan pektin dalam filtrat diendapkan dengan menggunakan
aseton atau etanol 96% (Ranggana, 2000). Menurut Megawati (2016)
pengendapan dilakukan karena pektin terlarut memiliki gangguan terhadap
kestabilan dispersi koloidalnya. Hal ini disebabkan karena pektin termasuk
koloidal hidrofilik yang bermuatan negatif (dari gugus karboksil bebas yang
terionisasi) dan tidak mempunyai titik isolistrik. Seperti koloid hidrofilik umumnya,
pektin distabilkan terutama oleh hidrasi partikelnya daripada oleh muatannya.
Pektin distabilkan oleh selapis air melalui ikatan elektrostatik antara muatan
negatif molekul pektin dan muatan positif molekul air. Penambahan zat
pendehidrasi seperti alkohol dapat mengurangi stabilitas dispersi pektin karena
efek dehidrasi mengganggu keseimbangan pektin-air, sehingga pektin akan
menggumpal.
14
Proses pencucian dilakukan agar senyawa pektin yang didapatkan bebas
dari senyawa-senyawa lain. Proses ini dilakukan dengan cara mencuci pektin
sebanyak dua kali dengan menggunakan etanol 96% (Sulihono, 2012).
Pengeringan dilakukan terhadap pektin basah untuk mengurangi kadar air
yang terkandung didalam pektin. Pengeringan dapat dilakukan menggunakan
oven dengan suhu 50oC selama 6 jam hingga pektin yang dihasilkan merupakan
pektin dalam bentuk kering (Perina, 2007).
2.2.5 Karakterisasi Pektin
Berikut adalah standar mutu pektin dan spesifikasi pektin berdasarkan
Standar Mutu International Pectin Producers Association (2002).
Tabel 2.2 Standar mutu pektin
Faktor Mutu Kandungan
Kandungan metoksil :
Pektin metoksil tinggi
Pektin bermetoksil rendah
Kadar asam galakturonat
Kadar abu
Kadar air
Derajat esterifikasi untuk :
Pektin ester tinggi
Pektin ester rendah
Berat Ekivalen
> 7,12%
2,5 - 7,12%
Min 35%
Maks 10%
Maks 12%
Min 50%
Maks 50%
600 – 800 mg
Sumber : Standar Mutu International Pectin Producers Association,
(2001)
2.2.5.1 Rendemen Pektin
Pektin merupakan salah satu kelompok kompleks heteropolisakarida
yang beragam. Pektin memiliki ukuran molekul yang beragam dan komposisi
yang berbeda sehingga struktur kimia dan molekulnya beragam. Komposisi
tersebut tergantung pada jenis bahan yang diekstrak, kondisi ekstraksi, lokasi
asal bahan dan faktor lingkungan yang lain (Chang, Dhurandhar dan Miyamoto
1994).
15
Rendemen pektin adalah jumlah kandungan pektin yang terdapat dalam
kulit pisang. Kandungan pektin yang dihasilkan tergantung pada jenis bahan
yang digunakan serta metode ekstraksinya (Nurhayati, 2015). Untuk
mendapatkan kadar pektin digunakan rumus berikut ini :
Rendemen Pektin = 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛 (𝑔)
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑝𝑢𝑛𝑔 𝑘𝑢𝑙𝑖𝑡 𝑝𝑖𝑠𝑎𝑛𝑔 (𝑔) x 100%
2.2.5.2 Berat Ekivalen
Berat ekivalen merupakan ukuran terhadap kandungan gugus asam
galakturonat bebas yang tidak teresterifikasi dalam rantai molekul pektin
(Ranganna, 1977). Asam pektat murni memiliki berat ekivalen 176 dan
seluruhnya tersusun dari asam poligalakturonat yang bebas dari gugus metil
ester atau tidak mengalami esterifikasi. Tingginya derajat esterifikasi antara asam
galakturonat dengan methanol akan menunjukkan semakin rendahnya jumlah
asam bebas yang berarti semakin tingginya berat ekivalen (Rouse, 1977). Untuk
mendapatkan berat ekuivalen digunakan rumus berikut ini :
Berat Ekivalen = 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛 (𝑚𝑔)
𝑚𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 𝑁 𝑁𝑎𝑂𝐻
2.2.5.3 Kadar Metoksil
Kadar metoksil dapat diartikan sebagai jumlah metanol yang terdapat di
dalam pektin. Pektin disebut bermetoksil tinggi jika memiliki nilai kadar metoksil
sama dengan 7,12% atau lebih. Jika kadar metoksil berkisar antara 2,5-7,12%
maka pektin disebut bermetoksil rendah (Goycoolea dan Adriana, 2003).
Kandungan metoksil pektin sangat berpengaruh terhadap pembentukan gel.
Pektin yang mengandung metoksil tinggi dapat membentuk gel dengan adanya
gula dan asam pada perbandingan tertentu sedangan pektin yang mengandung
metoksil rendah dapat membentuk gel tanpa adanya gula namun diperlukan
adanya penambahan kation polivalen seperti ion kalsium (Hastuti, 2016). Untuk
mendapatkan kadar metoksil digunakan rumus berikut ini :
Kadar metoksil (%) = 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 31 𝑥 𝑁 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 100
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
16
2.2.5.4 Kadar Galakturonat
Salah satu faktor yang menentukan mutu pektin adalah kadar
galakturonat yang dikandung di dalam pektin. Kerangka dasar penyusun
senyawa pektin adalah asam poligalakturonat dimana asam poligalakturonat ini
bisa menggambarkan kemurnian pektin. Jika asam poligalakturonat yang
dikandung semakin besar, maka kemurnian pektin tersebut semakin tinggi
karena kandungan organik lainnya seperti arabinosa, galaktosa, rhamnosa dan
jenis gula lainnya semakin kecil. Hal ini juga berpengaruh terhadap kemampuan
membentuk gel. Semakin banyak kandungan asam galakturonat yang ada, maka
jaringan tiga dimensi akan terbentuk dengan kokoh dan mampu menjebak
seluruh cairan yang ada di dalamnya sehingga gel yang terbentuk semakin kuat
(Sulihono, 2012). Jika berat ekuivalen dan kadar metoksil dari pektin sudah
diketahui maka kadar galakturonat bisa dihitung menggunakan rumus :
%Kadar galakturonat = 176 𝑥 0,1 𝑧 𝑥 100
𝑤 𝑥 1000 +
176 𝑥0,1 𝑦 𝑥 100
𝑤 𝑥 1000
Keterangan :
1 unit mol AUA = 176 g
Z = ml (titrasi) NaOH dari penentuan berat ekuivalen
Y = ml (titrasi) NaOH dari penentuan kadar metoksil
W = berat sampel
Kadar galakturonat dan muatan molekul pektin memiliki peranan penting
dalam menentukan sifat fungsional dari larutan pektin. Kadar galakturonat itu
sendiri mampu mempengaruhi struktur dan tekstur dari gel pektin (Constenla.
2006). Semakin tinggi kadar galakturonat yang dihasilkan maka mutu pektin juga
akan semakin tinggi (Haryati, 2006).
2.2.5.5 Derajat Esterifikasi
Derajat esterifikasi merupakan persentase jumlah residu asam D-
galakturonat yang gugus karboksilnya teresterifikasi dengan metanol (Haryati,
2006). Berdasarkan standar mutu pektin yang dikeluarkan oleh IPPA
(International Pectin Producers Assosiation), derajat esterifikasi terbagi atas 2
jenis yaitu pektin ester tinggi untuk yang memiliki nilai derajat esterifikasi minimal
50% dan pektin ester rendah untuk pektin yan memiliki nilai derajat esterifikasi
maksimal 50%. Nilai derajat esterifikasi pektin diperoleh dari nilai kadar metoksil
17
dan kadar asam galakturonat. Untuk mendapatkan nilai derajat esterifikasi
digunakan rumus berikut :
%DE = 176 𝑥 % 𝑀𝑒𝑂
31 𝑥 % 𝐴𝑈𝐴 x 100
2.2.5.6 Kadar Air
Masa simpan dari suatu bahan akan dipengaruhi oleh kadar air yang
terkandung di dalamnya. Tingginya kadar air yang dikandung oleh suatu bahan
akan menyebabkan kerentanan terhadap aktivitas mikroba (Hariyati, 2006).
Kadar air (%) = 𝑊𝑎−𝑊𝑏
𝑊 x 100%
Keterangan :
Wa = berat sebelum dikeringkan
Wb = berat akhir setelah dikeringkan
W = berat sampel awal
2.2.5.7 Kadar Abu
Abu adalah bahan anorganik yang didapatkan dari residu atau sisa
pembakaran suatu bahan organik. Kadar abu akan mempengaruhi tingkat
kemurnian pektin. Jika kadar abu dalam pektin semakin besar, maka persentase
kandungan pektin dan tingkat kemurnian yang terdapat di dalamnya akan
semakin rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar abu pektin dalam
suatu bahan adalah residu bahan anorganik yang terdapat pada bahan baku,
metode ekstraksi dan isolasi pektin (Kalapathy dan Proctor, 2001).
Prinsip penentuan kadar abu adalah bahan atau sampel akan dipanaskan
pada temperatur dimana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan
kemudian menguap, sehingga hanya unsur mineral dan anorganik yang akan
tertinggal (Departemen Kesehatan, 2000). Untuk mendapat kadar abu dalam
suatu bahan maka dapat digunakan rumus berikut ini :
Kadar Abu (%) = 𝑊1−𝑊2
𝑊 x 100%
Keterangan :
W = bobot sampel awal (g)
W1 = bobot wadah + sampel setelah pemanasan (g)
W2 = bobot wadah kosong (g)
18
2.3 Jenis Asam
Pemilihan jenis pelarut dalam proses ekstraksi perlu diperhatikan. Jenis
pelarut asam yang berbeda akan berhubungan dengan tingkat hidrolisis yang
berbeda. Hal itu disebabkan karena kekuatan asam yang berbeda akan
menghasilkan karakteristik pektin yang berbeda pula (Garna, 2007). Konsentrasi
serta jumlah pelarut juga akan berpengaruh terhadap efisiensi ekstraksi dan
dalam jumlah tertentu pelarut dapat bekerja secara optimal, namun jumlah yang
berlebihan tidak akan mengekstrak lebih banyak (Susanto, 1999).
2.3.1 Asam Klorida (HCl)
Asam klorida yang memiliki rumus kimia HCl merupakan salah satu asam
kuat yang banyak digunakan dalam industri. Larutan asam klorida (HCl) adalah
cairan kimia yang sangat korosif, bersifat volatil (mudah menguap), berbau
menyengat dan sangat iritatif, beracun dan termasuk bahan kimia berbahaya
atau B3. Asam klorida merupakan larutan gas hidrogen klorida (HCl) dalam air.
Warnanya bervariasi dari tidak berwarna hingga kuning muda. Perbedaan warna
ini tergantung pada kemurniannya. Asam klorida memiliki berat molekul 36,5
gr/mol, densitas 1,19 gr/ml, titik didih 50,50oC (1atm), titik lebur : -250C (1 atm),
serta dapat teroksidasi oleh oksidator kuat seperti MnO2, KmnO4, atau K2Cr2O7.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Syukron, 2015 didapatkan karakteristik
pektin dari kulit pisang Uli yang diekstrak menggunakan HCl sebagai berikut :
Tabel 2.3 Karakteristik Pektin Kulit Pisang Uli
No. Karakterisasi Waktu ekstraksi
70 menit 80 menit
1 Bobot pektin (gram) 2,05 2,45
2 Kadar air (%) 9,97 9,58
3 Kadar abu (%) 0,36 0,38
4 Berat ekivalen 5.260,942 3.642,191
5 Kadar metoksil (%) 3,07 3,20
6 Kadar galakturonat (%) 69,95 72,95
7 Derajat esterifikasi (%) 24,97 24,96
Sumber : (Syukron, 2015)
19
Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Castillo, 2015 didapatkan
karakteristik pektin dari kulit pisang Saba yang diekstrak menggunakan HCl
sebagai berikut :
Tabel 2.4 Karakteristik Pektin Kulit Pisang Saba
Karakteristik Tingkat kematangan
Matang Mentah
Rendemen pektin % 11.87 16.54 Kadar air % 10.00 14.13 Kadar abu % 11.15 13.83 Berat ekivalen 953.89 1503.16 Kadar metoksil % 6.40 5.25 Kadar galakturonat % 57.32 39.68 Derajat esterifikasi % 63.37 75.03
Sumber : (Castillo, 2015).
2.3.2 Asam Sitrat
Asam sitrat yang memiliki rumus kimia C6H8O7 adalah salah satu asam
organik yang sifatnya polar, mudah dicerna, tidak beracun, bersifat asam dan
mudah larut dalam air, spiritus dan etanol. Asam sitrat merupakan asam organik
yang berbentuk kristal atau serbuk putih serta memiliki nama IUPAC asam 2-
hidroksi-1,2,3-propanatrikarboksilat (Febrianty, 2007). Umumnya asam sitrat
digunakan sebagai bahan tambahan pangan ataupun sebagai bahan pengawet
dan merupakan bahan yang mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau.
Asam sitrat dapat mengikat logam-logam divalent seperti Mn2+. Fe2+. Cu2+
dan Mg2+. Asam sitrat dapat menghambat terjadinya pencoklatan karena
kemampuannya yang dapat membentuk kompleks dengan ion tembaga yang
berperan sebagai katalisator dalam reaksi pencoklatan. Selain itu asam sitrat
dapat mencegah terjadinya pencoklatan dengan cara menurunkan pH sehingga
enzim fenolase menjadi inaktif (Winarno, 2004). Berikut adalah gambar struktur
asam sitrat :
Gambar 2.9 Struktur asam sitrat
Sumber : (Febrianty, 2007)
20
III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biokimia, Laboratorium Teknologi
Pengolahan Pangan dan Laboratorium Bioteknologi Jurusan Teknologi Hasil
Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang, mulai
bulan Agustus 2017 hingga April 2018.
3.2 Alat dan Bahan Penelitian
3.2.1 Alat
Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain gelas beker,
erlenmeyer, gelas ukur, corong kaca, cawan petri, pengaduk kaca, bulb, pipet
ukur, pipet tetes, cabinet dryer, shaker water bath, sentrifuge, oven, desikator,
tanur, timbangan analitik, saringan kain, serta kertas saring halus.
3.2.2 Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepung kulit
pisang mentah, tepung kulit pisang setengah matang, tepung kulit pisang
matang, asam klorida (HCl), asam sitrat (C6H8O7), etanol 96% (teknis), aquades,
indikator fenol merah dan sodium hidroksida (NaOH).
3.3 Metode Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan
tiga faktor. Faktor 1 (tingkat kematangan pisang yang terdiri dari 3 level), faktor 2
(jenis pelarut yang terdiri dari 2 level) dan faktor 3 (konsentrasi pelarut yang
terdiri dari 3 level) dengan 2 kali ulangan sehingga diperoleh 36 satuan
percobaan.
(a) Tingkat kematangan pisang yaitu :
M1 = Mentah
M2 = Setengah matang
M3 = Matang
(b) Jenis pelarut yaitu :
A1 = HCl
A2 = Asam sitrat
(c) Konsentrasi pelarut yaitu :
K1 = 0,1 N
21
K2 = 0,2 N
K3 = 0,3 N
Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan Rancangan Percobaan:
Perlakuan HCl Asam sitrat
0,1 N 0,2 N 0,3 N 0,1 N 0,2 N 0,3 N
Mentah
M1A1K1 M1A1K2 M1A1K3 M1A2K1 M1A2K2 M1A2K3
Setengah
matang
M2A1K1 M2A1K2 M2A1K3 M2A2K1 M2A2K2 M2A2K3
Matang
M3A1K1 M3A1K2 M3A1K3 M3A2K1 M3A2K2 M3A2K3
Keterangan :
M1A1K1 = Mentah, HCl, 0,1 N
M1A1K2 = Mentah, HCl, 0,2 N
M1A1K3 = Mentah, HCl, 0,3 N
M1A2K1 = Mentah, Asam sitrat, 0,1 N
M1A2K2 = Mentah, Asam sitrat, 0,2 N
M1A2K3 = Mentah, Asam sitrat, 0,3 N
M2A1K1 = Setengah matang, HCl, 0,1 N
M2A1K2 = Setengah matang, HCl, 0,2 N
M2A1K3 = Setengah matang, HCl, 0,3 N
M2A2K1 = Setengah matang, Asam sitrat, 0,1 N
M2A2K2 = Setengah matang, Asam sitrat, 0,2 N
M2A2K3 = Setengah matang, Asam sitrat, 0,3 N
M3A1K1 = Matang, HCl, 0,1 N
M3A1K2 = Matang, HCl, 0,2 N
M3A1K3 = Matang, HCl, 0,3 N
M3A2K1 = Matang, Asam sitrat, 0,1 N
M3A2K2 = Matang, Asam sitrat, 0,2 N
M3A2K3 = Matang, Asam sitrat, 0,3 N
22
3.4 Pelaksanaan Penelitian
3.4.1 Pembuatan Tepung Kulit Pisang :
a. Kulit pisang yang digunakan dibedakan 3 tingkat kematangan yaitu kulit
pisang mentah, setengah matang dan matang. Kriteria kematangan
pisang ditentukan secara visual berdasarkan color chart yang terdapat
pada Lampiran 2.
b. Kulit pisang yang digunakan terlebih dahulu dipilih dan disortir dari kulit
pisang yang busuk atau rusak lalu dipotong kedua ujungnya.
c. Kulit pisang direndam di dalam sodium metabisulfit 100 ppm selama 15
menit untuk memperlambat terjadinya proses browning.
d. Kulit pisang di potong kecil-kecil yang bertujuan untuk memperbesar luas
permukaan sehingga ketika dikeringkan di cabinet dryer waktu yang
diperlukan tidak terlalu lama dan pengeringan dapat terjadi secara
merata.
e. Kulit pisang yang sudah dipotong-potong tersebut dikeringkan di cabinet
dryer pada suhu 45oC selama lebih kurang 11 jam.
f. Kulit pisang kemudian diblender dan diayak ukuran 80 mesh.
g. Setelah itu tepung kulit pisang ditimbang untuk mendapatkan rendemen
tepung kulit pisang.
3.4.2 Ekstraksi pektin :
a. Tepung kulit pisang ditimbang sebanyak 8 g kemudian ditambahkan
dengan pelarut asam dengan rasio 1:30 dan kemudian diekstrak
menggunakan hot water bath suhu 90oC selama 90 menit.
b. Ekstrak kemudian disaring dengan 2 lapis kain saring untuk memisahkan
filtrat dan residu.
Gambar 3.4.1.2 Pisang Candi Berdasarkan Tingkat Kematangan
Mentah Setengah Matang Matang
23
c. Kemudian filtrat di sentrifus dengan kecepatan 5000 xg selama 30 menit
untuk benar-benar memisahkan filtrat dari residu yang tersisa.
d. Selanjutnya filtrat yang didapatkan ditambahkan etanol teknis 96%
dengan perbandingan 1:2.
e. Pengendapan dilakukan pada suhu 4oC selama 24 jam.
f. Pektin yang menggumpal kemudian disaring dan dicuci dengan etanol
sebanyak 2 kali. Pencucian ini bertujuan untuk memurnikan pektin dari
residu-residu yang tersisa.
g. Kemudian pektin dikeringkan pada suhu 50oC selama 6 jam.
3.4.3 Analisa :
3.4.3.1 Analisa Bahan Baku
a. Kadar Protein (AOAC, 1995)
b. Kadar Air (AOAC, 1995)
c. Kadar Lemak (AOAC, 1995)
d. Kadar Abu (AOAC, 1995)
e. Kadar Karbohidrat (AOAC, 1995)
3.4.3.2 Karakterisasi Pektin
a. Persen rendemen (Raji, 2016)
b. Berat ekuivalen (Ranganna, 1995)
c. Kadar metoksil (Ranganna, 1995)
d. Kadar galakturonat (Ranganna, 1995)
e. Derajat esterifikasi (Ranganna, 1995)
f. Kadar air (AOAC, 1995)
g. Kadar abu (AOAC, 1955)
24
3.5 Analisa Data
Data yang sudah didapatkan akan dianalisa menggunakan ANOVA (Analysis of
Variance) dengan program Minitab 17 dan Excel 2010 dengan menggunakan
selang kepercayaan 95% (α = 0,05). Dari hasil uji ANOVA yang didapatkan akan
diketahui ada atau tidaknya pengaruh nyata dari faktor perlakuan yang diuji. Jika
hasil uji menunjukkan bahwa faktor tersebut beda nyata dan terjadi interaksi
antar faktor maka akan dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan Multiple Range
Test).
25
3.6 Diagram Alir
3.6.1 Persiapan Bahan
Penyortiran
Perendaman dalam sodium metabisulfit 100 ppm selama 15 menit
Pemotongan kecil-kecil
Pengeringan di cabinet dryer pada suhu 45oC selama 11 jam
Penghalusan dengan blender
Pengayakan dengan ayakan ukuran 80 mesh
Kulit pisang
Tepung kulit pisang
Gambar 3.1 Diagram Alir Persiapan Bahan (Modifikasi Emaga, 2007)
Analisa :
-Kadar Air
-Kadar Abu
-Protein
-Lemak
-Karbohidrat
-Rendemen pektin
26
3.6.2 Ekstraksi Pektin
Penimbangan sebanyak 8 gram
Dimasukkan kedalam hot water bath suhu 90oC selama 90 menit
Ekstrak
Penyaringan dengan 2 lapis kain saring
Filtrat
Pemisahan dengan sentrifuge dengan kecepatan 5000 xg selama 30 menit
Filtrat
Pengendapan pada suhu 40C selama 24 jam
Penyaringan
Pektin basah
Pencucian dengan etanol 96% 100ml sebanyak dua kali
Pektin basah
Pengeringan pada suhu 50oC
selama 6 jam
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tepung kulit pisang
Larutan asam 1:30
Residu
Residu
Pektin kering
Gambar 3.2 Diagram Alir Ekstraksi Pektin (Raji, 2016)
Etanol 96% dengan
perbandingan 1:2
Filtrat
Analisa :
-Rendemen Pektin
-Berat Ekivalen
-Kadar Metoksil
-Kadar Galakturonat
-Derajat Esterifikasi
-Kadar Air
-Kadar Abu
Analisa :
-Kadar Air
-Kadar Abu
-Warna
27
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Karakteristik Bahan Baku
Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini berupa kulit pisang
candi segar yang kemudian dilakukan analisa proksimat yakni pengujian kadar
protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, kadar air serta kadar abu. Hasil analisa
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.1 Karakteristik Kulit Pisang Candi Segar
Zat gizi Mentah Setengah matang Matang
Berat kulit tiap 100
gram buah (g)
43,49 39,63 44,46
Kadar air (%) 71,1±0,24 66,74±1,31 72,31±0,83
Kadar abu (%) 3,92±0,15 3,83±0,45 2,42±0,12
Protein (%) 7,12±0,07 7,59±0,29 5,71±0,12
Lemak (%) 4,34±0,07 6,82±0,09 5,58±0,63
Karbohidrat (%) 13,52±0,53 15,02±2,16 13,98±1,21
Rendemen pektin (%) 0,40±0,06 4,26±0,32 1,37±0,16
Dari Tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa limbah kulit pisang candi jumlahnya
mencapai kadar kurang lebih 40%. Hal ini menandakan bahwa limbah kulit
pisang candi memiliki jumlah yang cukup besar. Kandungan tertinggi dari kulit
pisang candi baik yang mentah, setengah matang maupun matang adalah air
dan karbohidrat. Kadar air yang dikandung oleh kulit pisang candi mencapai
kadar hingga 72% sedangkan kadar karbohidrat tertinggi dimiliki oleh kulit pisang
candi setengah matang dengan jumlah 15,02%. Menurut Linawati (2016) kulit
pisang mengandung kadar air sebesar 68,90%, karbohidrat sebesar 18,50%,
protein kasar sebesar 6-9% dan lemak kasar 3,8-11%.
4.2 Karakteristik Pektin Kulit Pisang Candi
4.2.1 Rendemen Pektin
Rendemen pektin yang dihasilkan dari penelitian ini berkisar antara
0,12% hingga 21,77%. Rendemen tertinggi didapatkan dengan ekstraksi pektin
dari kulit pisang mentah menggunakan asam sitrat dengan konsentrasi 0,2 N
28
sedangkan rendemen terendah didapatkan dengan ekstraksi pektin dari kulit
pisang matang menggunakan asam klorida dengan konsentrasi 0,3 N.
Berdasarkan analisa sidik ragam (α=0,05) yang terdapat pada Lampiran 3 dapat
diketahui bahwa tingkat kematangan yaitu mentah, setengah matang dan
matang, jenis asam yaitu asam klorida dan asam sitrat serta konsentrasi asam
0,1 N, 0,2 N dan 0,3 N berpengaruh nyata terhadap rendemen pektin yang
dihasilkan dari kulit pisang candi. Interaksi yang ditunjukkan oleh ketiga faktor
tersebut pun menunjukkan perbedaan yang nyata.
Tabel 4.2 Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi Asam terhadap
Rendemen Pektin Kulit Pisang Candi
Perlakuan Rerata
Rendemen (%)
DMRT
5% Jenis Asam Konsentrasi Tingkat Kematangan
Asam
Klorida (A1)
0,1 N (K1) Mentah (M1) 17,88± 1,06 h 1,27
Setengah matang (M2) 14,48 ± 1,33 g 1,27
Matang (M3) 8,99 ± 0,61 f 1,26
0,2 N (K2) Mentah (M1) 7,22 ± 0,00 e 1,25
Setengah matang (M2) 3,99 ± 0,20 cd 1,22
Matang (M3) 2,80 ± 0,04 b 1,18
0,3 N (K3) Mentah (M1) 2,94 ± 0,10 bc 1,20
Setengah matang (M2) 0,40 ± 0,01 a 1,14
Matang (M3) 0,12 ± 0,00 a 1,09
Asam Sitrat
(A2)
0,1 N (K1) Mentah (M1) 9,09 ± 0,53 f 1,27
Setengah matang (M2) 6,85 ± 0,61 e 1,24
Matang (M3) 4,61 ± 0,24 d 1,2
0,2 N (K2) Mentah (M1) 21,77 ± 0,36 i -
Setengah matang (M2) 14,52 ± 0,38 g 1,27
Matang (M3) 7,99 ± 0,55 ef 1,26
0,3 N (K3) Mentah (M1) 17,19 ± 0,12 h 1,27
Setengah matang (M2) 14,40 ± 0,45 g 1,27
Matang (M3) 6,98 ± 0,14 e 1,25
Sedangkan uji lanjut Duncan 5% yang terdapat pada Lampiran 4
menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan pektin dart kulit pisang matang
dengan asam klorida 0,3 N dan pektin dari kulit pisang setengah matang dengan
asam klorida 0,3 N tidak berbeda nyata dan kedua perlakuan ini menunjukkan
rendemen pektin yang terendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
29
Sedangkan kombinasi perlakuan pektin dari kulit pisang mentah dengan asam
klorida 0,1 dan pektin dari kulit pisang mentah dengan asam sitrat 0,2 N berbeda
nyata (α=0,05) dan kedua perlakuan ini menunjukkan rendemen pektin yang
tertinggi jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini menunjukkan
bahwa telah tercapainya kondisi optimum pada proses ekstraksi.
Berdasarkan grafik hubungan antara perlakuan dan rendemen pektin
diatas didapatkan bahwa untuk perlakuan menggunakan asam klorida, semakin
besar konsentrasi yang digunakan maka rendemen yang didapatkan cenderung
semakin menurun. Sedangkan untuk perlakuan yang menggunakan asam sitrat,
rendemen tertinggi dihasilkan pada konsentrasi 0,2 N dan selanjutnya cenderung
menurun ketika menggunakan konsentrasi 0,3 N.
Sedangkan semakin tinggi derajat keasaman suatu pelarut maka
rendemen pektin yang dihasilkan akan semakin besar (Sulihono, 2012). Menurut
Ningsih (2009) asam kuat akan melepaskan ion H+ lebih tinggi (atau terdisosiasi
sempurna) sehingga mampu mengekstrak lebih tinggi dibandingkan dengan
asam lemah. Prinsip ekstraksi pektin adalah perombakan protopektin yang tidak
larut menjadi pektin yang mudah larut yang dapat dilakukan dengan hidrolisis
asam atau enzimatis (Hanum, 2012). Pelarut asam klorida dan asam sitrat
Gambar 4.1 Grafik Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi
Asam terhadap Rendemen Pektin Kulit Pisang Candi
Konsentrasi Asam (N)
Rendem
en E
kstr
ak P
ektin (
%)
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
0.10 0.20 0.30
mentah (HCl)
setengah matang(HCl)
matang (HCl)
mentah (asam sitrat)
setengah matang(asam sitrat)
matang (asam sitrat)
30
merupakan asam yang berperan sebagai katalis untuk mempercepat reaksi
hidroliss protopektin menjadi pektin.
Semakin tinggi konsentrasi asam, maka semakin banyak kadar pektin
yang dihasilkan. Konsentrasi asam yang tinggi akan meningkatkan pelepasan
protopektin dari kulit pisang sehingga kadar pektin yang didapatkan semakin
besar pula (Fakhrizal, 2015). Semakin besarnya konsentrasi asam yang
ditambahkan, maka kemungkinan ion hidrogen untuk memutuskan ikatan
selulosa dengan asam pektinat akan semakin tinggi sehingga pektin yang larut
juga semakin besar. Konsentrasi serta jumlah pelarut akan berpengaruh
terhadap efisiensi ekstraksi dan dalam jumlah tertentu pelarut dapat bekerja
secara optimal, namun jumlah yang berlebihan tidak akan mengekstrak lebih
banyak (Susanto, 1999). Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikatakan jika
kondisi optimal untuk mengekstrak pektin menggunakan asam klorida adalah
menggunakan konsentrasi 0,1 N sedangkan konsentrasi optimal untuk asam
sitrat adalah 0,2 N.
Dari grafik pada Gambar 4.1 juga dapat dilihat jika rendemen pektin yang
dihasilkan cenderung menurun seiring dengan meningkatnya tingkat
kematangan. Hasil rendemen pektin tertinggi didapatkan dari kulit pisang
mentah, yakni sebesar 21,77 ± 0,36% dan hasil rendemen pektin terendah
didapatkan dari kulit pisang matang sebesar 0,12 ± 0,00%. Rendemen ekstrak
pektin akan menurun secara nyata dengan meningkatnya tingkat kematangan.
Menurut Kader (2002) rendahnya rendemen ekstrak pektin pada kulit pisang
yang lebih matang disebabkan karena pada umumnya buah-buahan mengalami
serangkaian perubahan komposisi kimia maupun fisiknya, diantaranya
perubahan kandungan asam-asam organik, gula dan karbohidrat lainnya.
Rendemen pektin pada kulit pisang yang sudah matang atau berwarna
kuning akan menurun jumlahnya karena proses degradasi pektin oleh enzim. Hal
ini sesuai dengan pendapat Winarno (2002) bahwa proses degradasi pektin,
banyak enzim yang dapat aktif, yaitu PE (pectin methyl esterase) yang aktif
dalam pemecahan metil dari metil ester, PG (polygalacturonase) yang membantu
memecahkan ikatan 1.4 dan PTE (pectin trans eliminase) yaitu enzim yang
bekerja pada ikatan 1.4 sama dengan PG tapi PTE bekerja pada hasil
hidrolisisnya. Hal ini didukung oleh penelitian Akili (2012) yang menemukan
jumlah pektin di dalam kulit pisang mentah dan matang berturut-turut 8,42%, dan
31
7.09%. Biasanya rendemen pektin juga dipengaruhi oleh sumber dan metode
ekstraksi yang digunakan (Rha, et. al, 2011).
4.2.2 Berat Ekivalen
Berat ekivalen merupakan ukuran terhadap kandungan gugus asam
galakturonat bebas yang tidak teresterifikasi dalam rantai molekul pektin. Berat
ekivalen pektin yang dihasilkan dari penelitian ini berkisar antara 787,45 hingga
10000 mg (milligram/ekivalen). Berat ekivalen tertinggi didapatkan dengan
ekstraksi pektin pada kulit pisang setengah matang menggunakan asam klorida
dengan konsentrasi 0,1 N sedangkan berat ekivalen terendah didapatkan
dengan ekstraksi pektin pada kulit pisang mentah menggunakan asam klorida
dengan konsentrasi 0,2 N.
Hasil dari analisa sidik ragam (α=0,05) yang terdapat pada Lampiran 6
adalah tingkat kematangan yaitu mentah, setengah matang dan matang, jenis
asam yaitu asam klorida dan asam sitrat serta konsentrasi asam 0,1 N, 0,2 N dan
0,3 N berpengaruh nyata terhadap berat ekivalen pektin yang dihasilkan dari kulit
pisang candi. Interaksi yang ditunjukkan oleh ketiga faktor tersebut pun
menunjukkan perbedaan yang nyata.
Sedangkan uji lanjut Duncan 5% yang terdapat pada Lampiran 7
menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan pektin dari kulit pisang mentah dengan
asam klorida 0,2 N dan pektin dari kulit pisang matang dengan asam klorida 0,2
N tidak berbeda nyata dan kedua perlakuan ini menunjukkan berat ekivalen
pektin yang terendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan
kombinasi perlakuan pektin dari kulit pisang setengah matang dengan asam
sitrat 0,1 N dan pektin dari kulit pisang setengah matang dengan asam klorida
0,1 N berbeda nyata dan kedua perlakuan ini menunjukkan berat ekivalen pektin
yang tertinggi jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
32
Tabel 4.3 Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi Asam terhadap
Berat Ekivalen Pektin Kulit Pisang Candi
Perlakuan Rerata Berat
Ekivalen
DMRT 5%
Jenis
Asam
Konsentrasi Tingkat
Kematangan
Asam Klorida
(A1)
0,1 N (K1)
Mentah (M1) 5902,78 ± 491,05 e 800,27
Setengah matang (M2) 10000,00 ± 0,00 f -
Matang (M3) 4356,06 ± 267,84 d 791,25
0,2 N (K2)
Mentah (M1) 787,45 ± 8,77 a 687,17
Setengah matang (M2) 1695,40 ± 40,64 b 767,89
Matang (M3) 1099,03 ± 17,08 ab 720,94
0,3 N (K3)
Mentah (M1) 4772,73 ± 321,41 d 796,80
Setengah matang (M2) 4356,06 ± 267,84 d 794,49
Matang (M3) 2704,68 ± 103,38 c 776,22
Asam Sitrat
(A2)
0,1 N (K1)
Mentah (M1) 6696,43 ± 631, 35 e 803,05
Setengah matang (M2) 6696,43 ± 631, 35 e 803,28
Matang (M3) 3229,17 ± 147,31 c 787,32
0,2 N (K2)
Mentah (M1) 4772,73 ± 321,41 d 798,89
Setengah matang (M2) 2859,48 ± 115,54 c 782,46
Matang (M3) 1352,34 ± 51,69 ab 742,45
0,3 N (K3)
Mentah (M1) 5902,78 ± 491,05 e 801,43
Setengah matang (M2) 5902,78 ± 491,05 e 802,36
Matang (M3) 1564,03 ± 69,12 b 757,25
Berat ekivalen pektin merupakan ukuran terhadap kandungan asam
galakturonat bebas yang tidak terestirifikasi di dalam rantai molekul pektin. Nilai
berat ekivalen ini ditentukan berdasarkan reaksi penyabunan gugus karboksil
oleh NaOH. Banyaknya volume NaOH yang digunakan dalam analisa
berbanding terbalik dengan nilai berat ekivalen. Semakin besar volume NaOH
yang digunakan maka semakin kecil berat ekivalen yang akan didapat sehingga
jumlah gugus karboksil yang tak teresterifikasi semakin banyak (Sulihono, 2012).
33
Nilai berat ekivalen berdasarkan standar mutu pektin adalah 600-800 mg.
Namun berdasarkan grafik hubungan antara perlakuan dan berat ekivalen pektin
pada Gambar 4.2 didapatkan bahwa untuk semua perlakuan baik menggunakan
asam klorida ataupun asam sitrat, cenderung memiliki nilai diatas 800 mg. Hanya
ada satu perlakuan yang memiliki berat ekivalen diantara rentang 600-800 mg
yaitu pektin dari kulit pisang mentah dengan menggunakan asam klorida 0,2 N
dengan nilai berat ekivalen 787,45 ± 8,77 mg.
Rendahnya berat ekivalen pada pektin menunjukkan kandungan asam
pektat yang ada pada pektin semakin tinggi. Asam pektat merupakan asam
galakturonat yang tidak teresterifikasi. Asam pektat banyak ditemukan pada buah
yang sudah terlalu matang sehingga berat ekivalen seharusnya menurun seiring
dengan meningkatnya tingkat kematangan. Roikah (2016) di dalam jurnalnya
yang berjudul Ekstraksi dan Karakterisasi Pektin Dari Belimbing Wuluh (Averrhoa
Bilimbi,L) mengatakan bahwa nilai berat ekivalen mengalami penurunan
kemungkinan karena belimbing wuluh sampel tercampur dengan belimbing wuluh
yang sudah matang yang mengandung banyak pektin yang kemudian mengalami
hidrolisis dari senyawa pektin menjadi asam pektat. Asam pektat murni tidak
Gambar 4.2 Grafik Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi
Asam terhadap Berat Ekivalen Pektin Kulit Pisang Candi
Konsentrasi Asam (N)
Bera
t E
kiv
ale
n (
mg)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
0.10 0.20 0.30
mentah (HCl)
setengah matang(HCl)
matang (HCl)
mentah (asamsitrat)
setengah matang(asam sitrat)
matang (asamsitrat)
34
mengalami esterifikasi sehingga merupakan gugus asam tanpa gugus metil
ester. Senyawa pektin yang tinggi gugus asam bebasnya dapat menurunkan
berat ekivalennya (Nurhikmat, 2003). Dapat dilihat pada grafik Gambar 4.2
bahwa pektin dari kulit pisang yang matang rata-rata memiliki nilai berat ekivalen
yang rendah. Esterifikasi akan menghasilkan gugus metil ester atau metoksil.
Maka tingkat kematangan, jenis asam dan konsentrasi asam akan berpengaruh
terhadap perbedaan kadar metoksil, kadar galakturonat dan derajat esterifikasi.
Pada grafik yang terdapat di Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa berat
ekivalen pektin yang diekstrak menggunakan asam klorida (asam kuat)
cenderung memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan pektin yang diekstrak
menggunakan asam sitrat (asam lemah). Menurut Erawati (2009) menyatakan
bahwa tingkat kekuatan asam yang lebih tinggi diduga menyebabkan probabilitas
reaksi depolimerisasi pektin meningkat. Dengan meningkatnya reaksi
depolimerisasi maka berat ekivalen pektin menjadi turun. Rendahnya berat
ekivalen pektin yang diekstrak menggunakan asam klorida disebabkan karena
asam klorida kekuatan asamnya lebih tinggi dibanding asam sitrat sehingga
pektin mengalami lebih banyak depolimerisasi.
Konsentrasi pelarut juga mempengaruhi berat ekivalen pektin yang
dihasilkan. Semakin tinggi konsentrasi asam pelarut, maka berat ekivalen
semakin rendah. Hal ini diduga karena semakin tinggi konsentrasi asam yang
digunakan memungkinkan terjadinya reaksi depolimerisasi pektin. Dengan
meningkatnya reaksi depolimerisasi maka berat ekivalen menjadi turun (Erawati,
2009). Selain itu konsentrasi asam yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya
deesterifikasi pektin menjadi asam pektat, dimana jumlah gugus asam bebas
akan semakin banyak sehingga berat ekivalen semakin rendah (Wijaksono,
2009). Hal lain yang mempengaruhi nilai berat ekivalen adalah sifat pektin hasil
ekstraksi itu sendiri, serta proses titrasi yang dilakukan (Fitria, 2013).
4.2.3 Kadar Metoksil
Kadar metoksil pektin yang dihasilkan dari penelitian ini berkisar antara
2,57% hingga 7,01%. Kadar metoksil tertinggi didapatkan dengan ekstraksi
pektin pada kulit pisang setengah matang menggunakan asam klorida dengan
konsentrasi 0,1 N sedangkan kadar metoksil terendah didapatkan dengan
ekstraksi pektin pada kulit pisang matang menggunakan asam sitrat dengan
konsentrasi 0,3 N.
35
Tabel 4.4 Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi Asam terhadap
Kadar Metoksil Pektin Kulit Pisang Candi
Perlakuan Rerata Kadar
Metoksil (%)
DMRT
5% Jenis Asam Konsentrasi Tingkat Kematangan
Asam
Klorida (A1)
0,1 N (K1) Mentah (M1) 5,77 ± 0,09 f 0,39
Setengah matang (M2) 7,01 ± 0,26 h -
Matang (M3) 5,05 ± 0,13 de 0,39
0,2 N (K2) Mentah (M1) 5,89 ± 0,09 f 0,39
Setengah matang (M2) 6,94 ± 0,18 h 0,40
Matang (M3) 4,00 ± 0,22 b 0,37
0,3 N (K3) Mentah (M1) 4,37 ± 0,04 c 0,38
Setengah matang (M2) 5,92 ± 0,13 fg 0,40
Matang (M3) 2,73 ± 0,18 a 0,36
Asam Sitrat
(A2)
0,1 N (K1) Mentah (M1) 6,01 ± 0,09 fg 0,40
Setengah matang (M2) 6,29 ± 0,13 gh 0,40
Matang (M3) 5,27 ± 0,09 e 0,39
0,2 N (K2) Mentah (M1) 6,11 ± 0,13 fgh 0,40
Setengah matang (M2) 6,42 ± 0,31 h 0,40
Matang (M3) 4,81 ± 0,13 d 0,38
0,3 N (K3) Mentah (M1) 6,05 ± 0,13 fgh 0,40
Setengah matang (M2) 5,74 ± 0,22 f 0,39
Matang (M3) 2,57 ± 0,13 a 0,34
Berdasarkan analisa sidik ragam (α=0,05) yang terdapat pada Lampiran
9 dapat diketahui bahwa tingkat kematangan yaitu mentah, setengah matang
dan matang, jenis asam yaitu asam klorida dan asam sitrat serta konsentrasi
asam 0,1 N, 0,2 N dan 0,3 N berpengaruh nyata terhadap kadar metoksil pektin
yang dihasilkan dari kulit pisang candi. Interaksi yang ditunjukkan oleh ketiga
faktor tersebut pun menunjukkan perbedaan yang nyata.
Sedangkan uji lanjut Duncan 5% yang terdapat pada Lampiran 10
menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan pektin dari kulit pisang matang dengan
asam sitrat 0,3 N dan pektin dari kulit pisang matang dengan asam klorida 0,3 N
tidak berbeda nyata dan kedua perlakuan ini menunjukkan kadar metoksil pektin
yang terendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan kombinasi
perlakuan pektin dari kulit pisang setengah matang dengan asam klorida 0,2 N
dan pektin dari kulit pisang setengah matang dengan asam klorida 0,1 N tidak
36
berbeda nyata dan kedua perlakuan ini menunjukkan kadar metoksil pektin yang
tertinggi jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
Berdasarkan grafik hubungan antara perlakuan dan kadar metoksil pektin
pada Gambar 4.3 didapatkan bahwa semua perlakuan cenderung memiliki kadar
metoksil dibawah 7,12%. Dimana menurut standar mutu pektin, jika pektin
memiliki kadar metoksil 2,5% - 7,12% maka pektin tersebut termasuk kedalam
pektin bermetoksil rendah. Hal ini dapat menjadi keuntungan karena pektin
bermetoksil rendah dapat langsung diproduksi tanpa melalui proses demetilasi
(Hanum, 2012).
Hasil dari grafik menunjukkan bahwa kandungan metoksil cenderung
menurun seiring dengan meningkatnya tingkat kematangan dari setengah
matang menjadi matang. Hal tersebut dapat terjadi karena ketika terjadi proses
pematangan, kadar gula buah meningkat dan kandungan metoksil menurun
(Sirisakulwat et al., 2008).
Ardiansyah (2014) mengatakan bahwa kadar metoksil meningkat
disebabkan karena pada tingkat keasaman yang rendah, reaksi hidrolisis tidak
efektif dan menyebabkan sedikit gugus ester yang hilang. Pemberian asam pada
ekstraksi pektin menyebabkan hidrolisis protopektin dan mengakibatkan
terjadinya pemutusan gugus ester dan pemutusan gugus metil. Sehingga dapat
Gambar 4.3 Grafik Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi
Asam terhadap Kadar Metoksil Pektin Kulit Pisang Candi
Konsentrasi Asam (N)
Kadar
Meto
ksil
(%)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0.10 0.20 0.30
mentah (HCl)
setengah matang(HCl)
matang (HCl)
mentah (asamsitrat)
setengah matang(asam sitrat)
matang (asamsitrat)
37
dilihat pada Gambar 4.3 bahwa pektin yang diekstrak menggunakan asam
klorida (asam kuat) cenderung memiiliki kadar metoksil yang lebih rendah
dibandingkan pektin yang diekstrak menggunakan asam lemah (asam sitrat).
Asam kuat akan melepaskan ion H+ lebih tinggi (atau terdisosiasi sempurna)
dibandingkan dengan asam lemah (Ningsih, 2009).
Grafik yang terdapat pada Gambar 4.3 didapatkan hasil bahwa kadar
metoksil tertinggi diperoleh dari ekstraksi dengan menggunakan asam klorida
dan kadar metoksil terendah diperoleh dari ekstraksi menggunakan asam sitrat.
Hal ini juga berkaitan dengan semakin besar konsentrasi asam yang digunakan
maka kadar metoksil cenderung semakin menurun. Hal itu disebabkan karena
semakin tingginya kekuatan asam maka pektin akan semakin cenderung
mengalami demetilasi. Penggunaan asam akan memberikan ion H+. Adanya ion
H+ pada larutan akan menyebabkan suasana asam yang akan mengakibatkan
terjadinya demetilasi. Ion H+ mampu mensubstitusi ikatan -CH3 pada gugus
metoksil dan mengubah gugus metoksil menjadi karboksil (Piknik, 1992).
Pektin bermetoksil rendah biasa digunakan dalam pembuatan saus salad,
puding, gel buah-buahan dalam es krim, selai, dan jeli. Pektin berkadar metoksil
rendah efektif digunakan dalam pembentukan gel saus buah-buahan beku
karena stabilitasnya yang tinggi pada proses pembekuan, thawing dan
pemanasan. Pektin bermetoksil rendah dapat membentuk gel dengan adanya
ion-ion logam bivalen, misalnya Ca2+, dimana ion bivalen ini dapat bereaksi
dengan gugus-gugus karboksil bebas dan membentuk jembatan. Pada
pembentukan gel ini tidak diperlukan kadar gula yang tinggi, oleh karena itu
pektin metoksil rendah biasanya digunakan untuk pembuatan jeli dan puding
berkalori rendah yang dimaksudkan untuk orang yang menghindari gula
(Daniarsari, 2005).
4.2.4 Kadar Galakturonat
Salah satu faktor yang menentukan mutu pektin adalah kadar
galakturonat yang dikandung di dalam pektin. Kerangka dasar penyusun
senyawa pektin adalah asam poligalakturonat dimana asam poligalakturonat ini
bisa menggambarkan kemurnian pektin. Jika asam poligalakturonat yang
dikandung semakin besar, maka kemurnian pektin tersebut semakin tinggi
karena kandungan organik lainnya seperti arabinosa, galaktosa, rhamnosa dan
jenis gula lainnya semakin kecil. Hal ini juga berpengaruh terhadap kemampuan
38
membentuk gel. Semakin banyak kandungan asam galakturonat yang ada, maka
jaringan tiga dimensi akan terbentuk dengan kokoh dan mampu menjebak
seluruh cairan yang ada didalamnya sehingga gel yang terbentuk semakin kuat
(Sulihono, 2012). Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Nurviani, (2014)
yaitu semakin tinggi kadar galakturonat, maka mutu pektin akan semakin tinggi
pula. Kadar galakturonat pektin yang dihasilkan dari penelitian ini berkisar antara
22% hingga 55,79%. Kadar galakturonat tertinggi didapatkan dengan ekstraksi
pektin pada kulit pisang mentah menggunakan asam klorida dengan konsentrasi
0,2 N sedangkan kadar metoksil terendah didapatkan dengan ekstraksi pektin
pada kulit pisang matang menggunakan asam klorida (HCl) dengan konsentrasi
0,3 N.
Tabel 4.5 Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi Asam terhadap
Kadar Galakturonat Pektin Kulit Pisang Candi
Perlakuan Rerata Kadar
Galakturonat (%)
DMRT
5% Jenis Asam Konsentrasi Tingkat Kematangan
Asam
Klorida (A1)
0,1 N (K1) Mentah (M1) 35,73 ± 0,25 cde 2,06
Setengah matang (M2) 41,54 ± 1,49 fg 2,11
Matang (M3) 32,74 ± 0,50 c 2,00
0,2 N (K2) Mentah (M1) 55,79 ± 0,25 i -
Setengah matang (M2) 49,81 ± 0,75 h 2,12
Matang (M3) 38,72 ± 1,00 ef 2,11
0,3 N (K3) Mentah (M1) 28,51 ± 0,50 c 1,96
Setengah matang (M2) 37,66 ± 0,50 def 2,09
Matang (M3) 22,00 ± 1,24 a 1,81
Asam Sitrat
(A2)
0,1 N (K1) Mentah (M1) 36,78 ± 0,25 cdef 2,07
Setengah matang (M2) 38,37 ± 1,00 def 2,10
Matang (M3) 35,38 ± 0,75 cd 2,02
0,2 N (K2) Mentah (M1) 38,37 ± 0,50 def 2,11
Setengah matang (M2) 42,59 ± 1,99 g 2,12
Matang (M3) 40,30 ± 0,25 ef 2,11
0,3 N (K3) Mentah (M1) 37,31 ± 0,50 def 2,09
Setengah matang (M2) 35,55 ± 1,00 cd 2,05
Matang (M3) 25,87 ± 0,25 b 1,90
Hasil dari analisa sidik ragam (α=0,05) yang terdapat pada Lampiran 12
adalah tingkat kematangan yaitu mentah, setengah matang dan matang, jenis
39
asam yaitu asam klorida dan asam sitrat serta konsentrasi asam 0,1 N, 0,2 N dan
0,3 N berpengaruh nyata terhadap kadar galakturonat pektin yang dihasilkan dari
kulit pisang candi. Interaksi yang ditunjukkan oleh ketiga faktor tersebut pun
menunjukkan perbedaan yang nyata.
Sedangkan uji lanjut Duncan 5% yang terdapat pada Lampiran 13
menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan pektin dari kulit pisang matang dengan
asam klorida 0,3 N dan pektin dari kulit pisang matang dengan asam sitrat 0,3 N
berbeda nyata dan kedua perlakuan ini menunjukkan kadar galakturonat pektin
yang terendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan kombinasi
perlakuan pektin dari kulit pisang setengah matang dengan asam klorida 0,2 N
dan pektin dari kulit pisang mentah dengan asam klorida 0,2 N berbeda nyata
dan kedua perlakuan ini menunjukkan kadar galakturonat pektin yang tertinggi
jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
Berdasarkan grafik hubungan antara perlakuan dan kadar galakturonat
pektin pada Gambar 4.4 didapatkan bahwa hampir semua perlakuan cenderung
memiliki kadar galakturonat diatas 35%. Dimana menurut standar mutu pektin,
seharusnya memiliki kadar galakturonat minimal 35%. Namun ada beberapa
Gambar 4.4 Grafik Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi
Asam terhadap Kadar Galakturonat Pektin Kulit Pisang Candi
Konsentrasi Asam (N)
Kadar
Gala
ktu
ronat
(%)
0
10
20
30
40
50
60
0.10 0.20 0.30
mentah (HCl)
setengah matang(HCl)
matang (HCL)
mentah (sitrat)
setengah matang(sitrat)
matang (sitrat)
40
perlakuan yang memiliki nilai kadar galakturonat dibawah 35%, yaitu pektin dari
kulit pisang matang dengan asam klorida 0,3 N, pektin dari kulit pisang matang
dengan asam sitrat 0,3 N, pektin dari kulit pisang mentah dengan asam klorida
0,3 N dan pektin dari kulit pisang matang dengan asam klorida 0,1 N. Rendahnya
nilai kadar galakturonat yang dikandung oleh pektin tersebut kemungkinan
disebabkan karena pektin yang diekstrak memiliki kadar protein, pati dan gula
yang tinggi (Ismail et al., 2012). Metode ekstraksi yang digunakan juga
mempengaruhi kadar galakturonat yang dikandung oleh pektin (Meilina, 2003).
Dari grafik dapat dilihat juga bahwa kadar galakturonat meningkat seiring
dengan meningkatnya konsentrasi asam dari 0,1 N ke 0,2 N. Namun cenderung
mengalami penurunan ketika menggunakan konsentrasi 0,3 N. Hal ini bisa
disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi maka semakin banyak ion H+
dimana ion H+ ini berfungsi memecahkan ikatan protopektin dengan senyawa-
senyawa dalam dinding sel kulit pisang dan menyatukan satu molekul pektin
dengan molekul pektin yang lain, sehingga terbentuk sebuah jaringan yang dapat
memerangkap air sehingga tekstur pektin yang dihasilkan saling terikat
(Constenla dan Lozano, 2003). Jika konsentrasi asam yang digunakan tinggi,
maka dalam proses ekstraksi ada kemungkinan senyawa lain yang ikut
terekstrak. Didalam jaringan, dinding sel terdiri dari 60% air dan 40% polimer. 20-
35% dari total polimer adalah pektin dimana asam galakturonat adalah
komponen penyusun utamanya. Senyawa lain yang terendapkan ini bisa saja
berupa senyawa non pektat atau merupakan bagian dari fraksi pektin seperti
gula. Komponen lain yang mungkin ikut terendapkan adalah protein (Garna,
2007).
Hasil yang didapatkan pada grafik di Gambar 4.4 menunjukkan bahwa
kadar galakturonat yang dihasilkan dari ekstraksi menggunakan asam klorida
(asam kuat) cenderung lebih besar daripada pektin yang diekstraksi
menggunakan asam sitrat (asam lemah). Hal ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Meilina (2003) yang mendapatkan hasil bahwa kadar galakturonat
untuk ekstraksi menggunakan asam klorida cenderung lebih tingi dibandingkan
dengan ekstraksi menggunakan asam sitrat. Menurut Wijaksono (2009),
meningkatnya kadar galakturonat ini dapat terjadi karena putusnya ikatan
komponen galakturonat pektin dengan senyawa-senyawa lain seperti
hemiselulosa. Dengan putusnya ikatan tersebut, maka senyawa lain tidak ikut
terendapkan pada proses pengendapan pektin. Semakin besar kekuatan asam,
41
maka semakin banyak ikatan yang dapat diputuskan sehingga hal ini dapat
meningkatkan persentase asam galakturonat.
Dari grafik yang terdapat pada Gambar 4.4 menunjukkan bahwa kadar
galakturonat pektin yang terendah cenderung didapatkan dari kulit pisang yang
matang. Hal ini sesuai dengan penelitian Azad (2014) yang mendapatkan kadar
galakturonat tertinggi pada pektin dari kulit jeruk lemon yang setengah matang
dan kadar galakturonat yang paling rendah didapatkan dari pektin kulit jeruk
lemon matang. Rendahnya nilai kadar galakturonat yang dikandung oleh pektin
tersebut kemungkinan disebabkan karena pektin yang diekstrak memiliki kadar
protein, pati dan gula yang tinggi (Ismail et al., 2012).
Perbedaan kadar galakturonat disebabkan oleh adanya senyawa-
senyawa lain seperti gula yang dapat terikut pada saat penggumpalan pektin
dengan alkohol. Hal ini didukung oleh pernyataan Nelson et al (1977) bahwa
pektin mengandung senyawa-senyawa lain yaitu gula netral seperti D-galaktosa,
L-arabinosa dan L-ramnosa. Senyawa tersebut dapat terikut pada waktu proses
penggumpalan pektin oleh alkohol.
4.2.5 Derajat Esterifikasi
Menurut standar mutu pektin, jika pektin memiliki derajat esterifikasi
diatas 50% maka pektin tersebut termasuk kedalam pektin ester tinggi. Jika
derajat esterifikasi yang dikandung oleh pektin berada dibawah 50% maka pektin
tersebut termasuk kedalam pektin ester rendah. Derajat esterifikasi pektin yang
dihasilkan dari penelitian ini berkisar antara 56,45% hingga 95,76%. Derajat
esterifikasi tertinggi didapatkan dengan ekstraksi pektin pada kulit pisang
setengah matang menggunakan asam klorida dengan konsentrasi 0,1 N
sedangkan kadar metoksil terendah didapatkan dengan ekstraksi pektin pada
kulit pisang matang menggunakan asam sitrat dengan konsentrasi 0,3 N.
Berdasarkan analisa sidik ragam (α=0,05) yang terdapat pada Lampiran
15 dapat diketahui tingkat kematangan yaitu mentah, setengah matang dan
matang, jenis asam yaitu asam klorida dan asam sitrat serta konsentrasi asam
0,1 N, 0,2 N dan 0,3 N berpengaruh nyata terhadap derajat esterifikasi pektin
yang dihasilkan dari kulit pisang candi. Interaksi yang ditunjukkan oleh ketiga
faktor tersebut pun menunjukkan perbedaan yang nyata.
42
Tabel 4.6 Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi Asam terhadap
Derajat Esterifikasi Pektin Kulit Pisang Candi
Perlakuan Rerata Derajat
Esterifikasi (%)
DMRT
5% Jenis Asam Konsentrasi Tingkat Kematangan
Asam
Klorida (A1)
0,1 N (K1) Mentah (M1) 91,62 ± 0,76 hij 2,40
Setengah matang (M2) 95,76 ± 0,15 k -
Matang (M3) 87,63 ± 0,95 fg 2,38
0,2 N (K2) Mentah (M1) 59,94 ± 0,62 b 2,22
Setengah matang (M2) 79,15 ± 0,81 d 2,33
Matang (M3) 58,61 ± 1,71 b 2,16
0,3 N (K3) Mentah (M1) 87,04 ± 0,65 fg 2,37
Setengah matang (M2) 89,25 ± 0,80 gh 2,39
Matang (M3) 70,39 ± 0,54 d 2,30
Asam Sitrat
(A2)
0,1 N (K1) Mentah (M1) 92,82 ± 0,73 j 2,41
Setengah matang (M2) 93,13 ± 0,47 j 2,41
Matang (M3) 84,58 ± 0,38 e 2,34
0,2 N (K2) Mentah (M1) 90,36 ± 0,77 hi 2,39
Setengah matang (M2) 85,54 ± 0,09 ef 2,36
Matang (M3) 67,68 ± 1,43 c 2,27
0,3 N (K3) Mentah (M1) 91,98 ± 0,77 hij 2,40
Setengah matang (M2) 91,57 ± 0,94 hij 2,40
Matang (M3) 56,45 ± 2,34 a 2,06
Sedangkan uji lanjut Duncan 5% yang terdapat pada Lampiran 16
menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan pektin dari kulit pisang matang dengan
asam sitrat 0,3 N dan pektin dari kulit pisang matang dengan asam klorida 0,2 N
berbeda nyata dan kedua perlakuan ini menunjukkan derajat esterifikasi pektin
yang terendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan kombinasi
perlakuan pektin dari kulit pisang setengah matang dengan asam sitrat 0,1 N dan
pektin dari kulit pisang setengah matang dengan asam klorida 0,1 N berbeda
nyata dan kedua perlakuan ini menunjukkan derajat esterifikasi pektin yang
tertinggi jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
43
Berdasarkan grafik hubungan antara perlakuan dan derajat esterifikasi
pektin pada Gambar 4.5 yang didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan
rumus :
%DE = 176 𝑥 % 𝑀𝑒𝑂
31 𝑥 % 𝐴𝑈𝐴 x 100
didapatkan bahwa semua perlakuan cenderung memiliki derajat esterifikasi
diatas 50%. Pektin yang dihasilkan pada penelitian ini merupakan pektin
bermetoksil rendah dengan rentang kadar metoksil 2,57% hingga 7,01%. Karena
derajat esterifikasi didapatkan dari hasil kadar metoksil yang dibagi dengan kadar
galakturonat, maka kadar metoksil dan kadar galakturonat akan mempengaruhi
hasil dari derajat esterifikasi. Hasil derajat esterifikasi yang diinginkan adalah
dibawah 50% karena kaitannya dengan kadar metoksil yang dihasilkan. Namun
yang didapatkan pada penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang ada. Karena
menurut teori yang ada, derajat esterifikasi yang dihasilkan dari pektin
bermetoksil rendah memiliki derajat esterifikasi yang rendah pula yakni memiliki
nilai dibawah 50%, namun pada hasil penelitian ini semua perlakuan memiliki
derajat esterifikasi diatas 50%. Hal ini dapat terjadi karena kadar galakturonat
yang dihasilkan oleh pektin dalam penelitian ini memiliki nilai yang rendah yang
berarti masih banyak komponen lain yang ikut terlarut di dalam proses ekstraksi
Gambar 4.5 Grafik Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi
Asam terhadap Derajat Esterifikasi Pektin Kulit Pisang Candi
Konsentrasi Asam (N)
Dera
jat
Este
rifikasi (%
)
0
20
40
60
80
100
120
0.10 0.20 0.30
mentah (HCl)
setengah matang(HCl)
matang (HCL)
mentah (sitrat)
setengah matang(sitrat)
matang (sitrat)
44
pektin seperti senyawa non pektat atau merupakan bagian dari fraksi pektin
seperti gula. Komponen lain yang mungkin ikut terendapkan adalah protein
(Garna, 2007). Secara umum, perubahan derajat esterifikasi di pektin pada
proses pematangan buah biasanya dipengaruhi juga oleh jenis tanaman, tipe
pektin dan aktivitas pektin metilesterase (Ding, et.al, 2017).
Hasil dari grafik menunjukkan bahwa derajat esterifikasi menurun seiring
dengan meningkatnya tingkat kematangan. Semakin rendah derajat esterifikasi
kemungkinan disebabkan karena perubahan protopektin menjadi pektin yang
akan meningkatkan gula dan membuat buah lebih lunak selama pematangan
(Redgwell et al., 1997). Namun Sundar et al. (2012) mengatakan bahwa derajat
esterifikasi dalam pektin sebenarnya tergantung pada spesies, jaringan dan
tingkat kematangan.
4.2.6 Kadar air
Kadar air merupakan salah satu faktor penting yang menentukan daya
tahan produk karena kaitannya dengan aktivitas mikroorganisme selama
penyimpanan. Produk yang memiliki kadar air tinggi akan lebih kondusif untuk
pertumbuhan mikroorganisme akan menyebabkan produk tersebut lebih cepat
rusak (Ningsih, 2009).
Kadar air pektin yang dihasilkan dari penelitian ini berkisar antara 6,98%
hingga 9,81%. Kadar air tertinggi didapatkan dengan ekstraksi pektin pada kulit
pisang mentah menggunakan asam klorida dengan konsentrasi 0,2 N sedangkan
kadar metoksil terendah didapatkan dengan ekstraksi pektin pada kulit pisang
setengah matang menggunakan asam klorida dengan konsentrasi 0,3 N.
Hasil dari analisa sidik ragam (α=0,05) yang terdapat pada Lampiran 18
adalah tingkat kematangan yaitu mentah, setengah matang dan matang, jenis
asam yaitu asam klorida dan asam sitrat serta konsentrasi asam 0,1 N, 0,2 N dan
0,3 N tidak berpengaruh terhadap kadar air pektin yang dihasilkan dari kulit
pisang candi. Namun interaksi yang ditunjukkan oleh ketiga faktor tersebut
menunjukkan perbedaan yang nyata.
45
Tabel 4.7 Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi Asam terhadap
Kadar Air Pektin Kulit Pisang Candi
Perlakuan Rerata Kadar Air
(%)
DMRT
5% Jenis Asam Konsentrasi Tingkat Kematangan
Asam
Klorida (A1)
0,1 N (K1) Mentah (M1) 8,84 ± 0,39 efg 0,94
Setengah matang (M2) 7,57 ± 0,19 abcd 0,90
Matang (M3) 7,13 ± 0,16 ab 0,85
0,2 N (K2) Mentah (M1) 9,81 ± 0,07 h -
Setengah matang (M2) 8,83 ± 0,61 efg 0,94
Matang (M3) 8,06 ± 0,62 cde 0,93
0,3 N (K3) Mentah (M1) 8,79 ± 0,39 efg 0,94
Setengah matang (M2) 6,98 ± 0,66 a 0,81
Matang (M3) 9,19 ± 0,22 fgh 0,94
Asam Sitrat
(A2)
0,1 N (K1) Mentah (M1) 7,81 ± 0,27 bcd 0,93
Setengah matang (M2) 9,66 ± 0,17 h 0,94
Matang (M3) 9,15 ± 0,17 fgh 0,94
0,2 N (K2) Mentah (M1) 7,40 ± 0,04 abc 0,87
Setengah matang (M2) 7,43 ± 0,00 abc 0,89
Matang (M3) 8,36 ± 0,36 def 0,94
0,3 N (K3) Mentah (M1) 7,71 ± 0,20 abcd 0,92
Setengah matang (M2) 7,69 ± 0,77 abcd 0,91
Matang (M3) 8,20 ± 0,40 cde 0,93
Sedangkan uji lanjut Duncan 5% yang terdapat pada Lampiran 19 menunjukkan
bahwa kombinasi perlakuan pektin dari kulit pisang setengah matang dengan
asam klorida 0,3 N dan pektin dari kulit pisang matang dengan asam klorida 0,1
N tidak berbeda nyata dan kedua perlakuan ini menunjukkan kadar air pektin
yang terendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan kombinasi
perlakuan pektin dari kulit pisang setengan matang dengan asam sitrat 0,1 N dan
pektin dari kulit pisang mentah dengan asam klorida 0,2 N tidak berbeda nyata
dan kedua perlakuan ini menunjukkan kadar air pektin yang tertinggi jika
dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
46
Berdasarkan grafik hubungan antara perlakuan dan kadar air pektin pada
Gambar 4.6 didapatkan bahwa semua perlakuan cenderung memiliki kadar air
dibawah 12%. Dimana hasil tersebut sesuai dengan standar mutu pektin yang
menyebutkan bahwa kadar air pektin maksimal adalah 12%.
Tingginya kadar air pada suatu bahan akan menyebabkan kerentanan
terhadap aktivitas mikroba serta berpengaruh terhadap umur simpan dari bahan
tersebut. Produk dengan kadar air rendah relatif lebih stabil dalam penyimpan
jangka panjang daripada produk yang berkadar air tinggi (Nurviani, 2014). Kadar
air yang tinggi juga bisa memungkinkan terjadinya pertumbuhan mikroorganisme
dan produksi enzim pektinase yang nantinya akan berdampak pada kualitas
pektin (Muhammadzadeh, 2010). Kadar air pektin lebih banyak dipengaruhi oleh
derajat pengeringan endapan pektin dan kondisi penyimpanannya (Meilina,
2003).
4.2.7 Kadar Abu
Abu adalah bahan anorganik yang didapatkan dari sisa atau residu
pembakaran bahan organik. Kandungan mineral suatu bahan dapat diketahui
dari kadar abu yang dimiliki oleh bahan tersebut. Faktor-faktor yang
Gambar 4.6 Grafik Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi
Asam terhadap Kadar Air Pektin Kulit Pisang Candi
Konsentrasi Asam (N)
Kadar
Air (
%)
0
2
4
6
8
10
12
0.10 0.20 0.30
mentah (HCl)
setengah matang(HCl)
matang (HCL)
mentah (sitrat)
setengah matang(sitrat)
matang (sitrat)
47
mempengaruhi kadar abu dalam pektin adalah residu bahan anorganik yang
terkandung dalam bahan baku, metode ekstraksi serta isolasi pektin (Kalapathy,
2001).
Kadar abu pektin yang dihasilkan dari penelitian ini berkisar antara 0,13%
hingga 8,88%. Kadar abu tertinggi didapatkan dengan ekstraksi pektin pada kulit
pisang matang menggunakan asam klorida dengan konsentrasi 0,3 N
sedangkan kadar abu terendah didapatkan dengan ekstraksi pektin pada kulit
pisang mentah menggunakan asam sitrat dengan konsentrasi 0,1 N. Menurut
IPPA (2002) batas dari kadar abu di dalam pektin adalah 10%. Hal ini
menunjukkan bahwa kadar abu pektin dari hasil penelitian ini masih termasuk ke
dalam batas yang diperbolehkan oleh IPPA (International Pectin Producers
Association).
Tabel 4.8 Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi Asam terhadap
Kadar Abu Pektin Kulit Pisang Candi
Perlakuan Rerata Kadar Abu
(%)
DMRT
5% Jenis Asam Konsentrasi Tingkat Kematangan
Asam
Klorida (A1)
0,1 N (K1) Mentah (M1) 3,19 ± 0,05 g 0,37
Setengah matang (M2) 2,72 ± 0,14 f 0,37
Matang (M3) 5,56 ± 0,22 j 0,37
0,2 N (K2) Mentah (M1) 4,26 ± 0,13 i 0,37
Setengah matang (M2) 3,79 ± 0,18 h 0,37
Matang (M3) 6,87 ± 0,07 k 0,37
0,3 N (K3) Mentah (M1) 5,48 ± 0,27 j 0,37
Setengah matang (M2) 4,37 ± 0,30 i 0,37
Matang (M3) 8,88 ± 0,14 l -
Asam Sitrat
(A2)
0,1 N (K1) Mentah (M1) 0,13 ± 0,00 a 0,32
Setengah matang (M2) 0,78 ± 0,04 cd 0,35
Matang (M3) 0,34 ± 0,00 ab 0,33
0,2 N (K2) Mentah (M1) 0,48 ± 0,04 bc 0,34
Setengah matang (M2) 0,92 ± 0,02 de 0,36
Matang (M3) 2,36 ± 0,16 f 0,36
0,3 N (K3) Mentah (M1) 1,11 ± 0,09 e 0,36
Setengah matang (M2) 5,64 ± 0,15 j 0,37
Matang (M3) 2,63 ± 0,22 f 0,37
48
Berdasarkan analisa sidik ragam (α=0,05) yang terdapat pada Lampiran
21 dapat diketahui bahwa tingkat kematangan yaitu mentah, setengah matang
dan matang, jenis asam yaitu asam klorida dan asam sitrat serta konsentrasi
asam 0,1 N, 0,2 N dan 0,3 N berpengaruh nyata terhadap kadar abu pektin yang
dihasilkan dari kulit pisang candi. Interaksi yang ditunjukkan oleh ketiga faktor
tersebut pun menunjukkan perbedaan yang nyata.
Uji lanjut Duncan 5% yang terdapat pada Lampiran 22 menunjukkan
bahwa kombinasi perlakuan pektin dari kulit pisang mentah dengan asam sitrat
0,1 N dan pektin dari kulit pisang matang dengan asam sitrat 0,1 N tidak berbeda
nyata dan kedua perlakuan ini menunjukkan kadar abu pektin yang terendah
dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan kombinasi perlakuan pektin
dari kulit pisang matang dengan asam klorida 0,2 N dan pektin dari kulit pisang
matang dengan asam klorida 0,3 N berbeda nyata dan kedua perlakuan ini
menunjukkan kadar abu pektin yang tertinggi jika dibandingkan dengan
perlakuan lainnya.
Berdasarkan grafik hubungan antara perlakuan dan kadar abu pektin
pada Gambar 4.7 didapatkan bahwa untuk semua perlakuan baik menggunakan
asam klorida ataupun asam sitrat, jika konsentrasi asam semakin besar maka
Gambar 4.7 Grafik Pengaruh Tingkat Kematangan, Jenis Asam dan Konsentrasi
Asam terhadap Derajat Esterifikasi Pektin Kulit Pisang Candi
Konsentrasi Asam (N)
Kadar
Abu (
%)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.10 0.20 0.30
mentah (HCl)
setengah matang(HCl)
matang (HCL)
mentah (sitrat)
setengah matang(sitrat)
matang (sitrat)
49
kadar abu pun semakin besar. Namun dapat dilihat pada grafik bahwa semua
perlakuan cenderung memiliki kadar abu dibawah 10% dimana hal itu sesuai
dengan standar mutu pektin yang menyebutkan bahwa kadar abu maksimal
pada pektin adalah 10%.
Grafik juga menunjukkan bahwa kadar abu dalam pektin tertinggi
didapatkan dari sampel kulit pisang matang yaitu sebesar 8,88 ± 0,14%
sedangkan kadar abu dalam pektin terendah didapatkan dari sampel mentah
yaitu sebesar 0,13 ± 0,00%. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyatakan
bahwa kadar abu yang dikandung oleh pektin akan meningkat seiring dengan
menurunnya rendemen pektin yang dihasilkan, hal ini menunjukkan bahwa
kandungan gula dan kompenen lainnya meningkat seiring dengan terjadinya
proses pematangan pada buah.
Grafik yang terdapat pada Gambar 4.7 dapat dilihat bahwa kadar abu
cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kematangan. Kadar
abu tertinggi didapatkan pada pektin dari kulit pisang matang yakni sebesar 8,88
± 0,14% dan kadar abu terendah didapatkan dari pektin yang dihasilkan dari kulit
pisang mentah yakni sebesar 0,13 ± 0,00%. Hal ini disebabkan karena
kandungan gula dan komponen lainnya juga meningkat secara signifikan proses
karena pematangan buah (Azad, 2014).
Jenis asam yang digunakan berpengaruh terhadap kadar abu pektin yang
dihasilkan. Asam klorida yang termasuk asam kuat cenderung memiliki kadar
abu yang lebih besar dari pektin yang diekstrak menggunakan asam sitrat. Hal ini
terjadi karena adanya reaksi hidrolisis protopektin. Hidrolisis protopektin
menyebabkan bertambahnya kandungan kalsium dan magnesium. Kalsium dan
magnesium merupakan mineral sebagai komponen abu. Dengan demikian
semakin banyaknya mineral berupa kalsium dan magnesium akan semakin
banyak kadar abu pektin tersebut (Budiyanto, 2008). Menurut Ningsih (2009)
asam kuat akan melepaskan ion H+ lebih tinggi (atau terdisosiasi sempurna)
sehingga mampu mengekstrak lebih tinggi dibandingkan dengan asam lemah.
Kadar abu didalam pektin akan semakin meningkat jumlahnya seiring
dengan meningkatnya konsentrasi asam, suhu dan waktu ekstraksi. Hal itu
dikarenakan kemampuan asam untuk melarutkan mineral alami dari bahan yang
diekstrak akan meningkat seiring meningkatnya konsentrasi asam, suhu dan
waktu ekstraksi. Mineral yang terlarut akan ikut mengendap bercampur dengan
pektin pada saat pengendapan dengan alkohol (Kalapathy, 2001). Hasil yang
50
didapatkan dari penelitian ini sesuai dengan pernyataan diatas dimana
konsentrasi asam tertinggi menghasilkan kadar abu yang tertinggi.
51
V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan :
1. Tingkat kematangan pada proses ekstraksi pektin berpengaruh nyata (α =
0,05) terhadap karakteristik pektin yang dihasilkan. Semakin matang
pisang maka cenderung menurunkan rendemen ektstrak pektin,
menurunkan berat ekivalen, menurunkan kadar metoksil, menurunkan
kadar galakturonat, menurunkan derajat esterifikasi dan meningkatkan
kadar abu.
2. Jenis asam pada proses ekstraksi pektin berpengaruh nyata (α = 0,05)
terhadap karakteristik pektin yang dihasilkan. Asam yang lebih kuat
cenderung menurunkan rendemen ekstrak pektin, menurunkan berat
ekivalen, menurunkan kadar metoksil, meningkatkan kadar galakturonat,
menurunkan derajat esterifikasi dan meningkatkan kadar abu.
3. Konsentrasi asam pada proses ekstraksi pektin berpengaruh nyata (α =
0,05) terhadap karakteristik pektin yang dihasilkan. Semakin besar
konsentrasi yang digunakan cenderung meningkatkan rendemen ekstrak
pektin, menurukan berat ekivalen, menurunkan kadar metoksil,
menurunkan kadar galakturonat, menurunkan derajat esterifikasi dan
meningkatkan kadar abu.
4. Berdasarkan analisa sidik ragam (α=0,05) terjadi interaksi antara tingkat
kematangan, jenis asam dan konsentrasi asam yang digunakan pada
rendemen pektin, berat ekivalen, kadar metoksil, kadar galakturonat,
derajat esterifikasi, kadar air dan kadar abu.
5. Pektin hasil ekstraksi dari kulit pisang candi termasuk kedalam jenis
pektin bermetoksil rendah.
5.2 Saran
Saran dari penelitian ini adalah :
1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang metode ekstraksi dan kondisi
ekstraksi yang optimal sehingga menghasilkan karakteristik pektin yang
lebih baik.
2. Perlu adanya penelitian tentang cara memurnikan pektin lebih lanjut
sehingga pektin yang dihasilkan lebih baik.
52
DAFTAR PUSTAKA
Abid, M., Cheikhrouhou, S., Renard, C.M., Bureau, S., Cuvelier, G., Attia, H., and
Ayadi, M. 2016. Characterization of Pectins Extracted from
Pomegranate Peel and Their Gelling Properties. Food Chemistry 215
(2017) 318–325.
Agoes, G. 2007. Teknologi Bahan Alam. Bandung : ITB Press.
Akili, M.S., Ahmad, U., dan Suyatma, N.E. 2012. Karakteristik Edible Film dari
Pektin Hasil Ekstraksi Kulit Pisang. Jurnal Keteknikan Pertanian Vol.
26, No. 1.
Ansel, H.C. 1989, Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi, diterjemahkan oleh
Farida Ibrahim, Asmanizar, Iis Aisyah, Edisi keempat, 255-271, 607-608,
700. Jakarta : UI Press.
AOAC. 1995. Official Methods of Analysis of The Association of Analytical
Chemists. Washington D.C
Ardiansyah, G., Hamzah, F dan Efendi, R. 2014. Variasi Tingkat Keasaman
dalam Ekstraksi Pektin Kulit Buah Durian. JOM FAPERTA Vol. 1 No
2 Oktober 2014
Azad, A. K. M., Ali,M. A., Akter, M.S., Rahman, M.J., Ahmed, M. 2014. Isolation
and Characterization of Pectin Extracted from Lemon Pomace
During Ripening. Journal of Food and Nutrition Sciences 2014; 2(2):
30-35.
Badan Pusat Statistik.2016. http ://www.pertanian.go.id/Data5tahun/HortiATAP20
16/Produksi%20Pisang.pdf . Diakses pada 13 Februari 2018.
Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Jatim. 1982. Laporan Hasil
Penelitian. Laboratorium Dinas Perindustrian. Surabaya.
Budiyanto, A., dan Yulianingsih. 2008. Pengaruh Suhu dan Waktu Ekstraksi
terhadap Karakter Pektin dari Ampas Jeruk Siam (Citrus nobilis L).
Jurnal Penelitian Pascapanen Pertanian 5(2).
Castillo, I.K.A.T., Baguio, S.F., Diasanta, M.D.B., Lizardo, R.C.M., Dizon, E.I. and
Mejico, M.I.F. 2015. Extraction and Characterization of Pectin from
Saba Banana [Musa ‘saba’(Musa acuminata x Musa balbisiana)]
Peel Wastes: A Preliminary Study. International Food Research
Journal 22(1): 202-207.
53
Chang, K. C., Dhurandhar, N., You, X. dan Miyamoto, A. 1994. Cultivar/
Location and Processing Methods Affect The Quality of Sun Flower
Pectin. J. Food Sci., 59: 602-612.
Constenla, D., Ponce, A.G., and Lozano, J.E. 2002. Effect of Pomace Drying
on Apple Pectin. Lebensmittel Wissenschaft und Technology. 35(3):
216-221.
Ding, S., Wang, R., Dan, Yang., Li, Gaoyang., and Ou, S. 2017. Changes in
Pectin Characteristics During The Ripening of Jujube Fruit. China :
Hunan Agricultural Product Processing Institute
Daryono, E.D. 2012. Ekstraksi Pektin dari Labu Siam. Jurnal Teknik Kimia
Vol.7, No.1, September 2012.
Daniarsari, I., dan Hidajati, N. 2005. Pengaruh Suhu Ekstraksi Terhadap
Rendement dan Kadar Metoksil Pektin dari Eceng Gondo
(Eichornia crassipes (Mart Solms). Indo. J. Chem., 2005, 5 (3), 232 –
235.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2000. Parameter Standar Umum
Ekstrak Tumbuhan Obat, Edisi I. Jakarta : Direktorat Jendral POM.
Erawati, F. 2009. Ekstraksi dan Karakterisasi Pektin Kulit Pisang Kajian
Jenis Pelarut Asam dan Rasio Bahan : Pelarut Asam. Skripsi.
Malang : Universitas Brawijaya
Fakhrizal., Fauzi. R., dan Ristianingsih, Y. 2015. Pengaruh Konsentrasi Pelarut
HCl pada Ekstraksi Pektin dari Kulit Pisang Ambon. Konversi,
Volume 4 No. 2, Oktober 2015
Febrianty, A dan Suryadi. 2007. Fermentasi Limbah Jeruk Menjadi Asam
Sitrat. Inderalaya : Universitas Sriwijaya.
Febriyanti, Y., Razak, A.R., dan Sumarni, N.K. 2018. Ekstraksi dan
Karakterisasi Pektin dari Kulit Buah Kluwih (Artocarpus camansi
Blanco). KOVALEN, 4(1): 60-73
Fellows, P. 2002. Food Processing Technology Edisi 2. London : Woodhead
Publishing Limited.
Fitria, V. 2013. Karakterisasi Pektin Hasil Ekstraksi dari Limbah Kulit Pisang
Kepok (Musa balbisiana ABB). Skripsi. Jakarta : UIN Syarif
Hidayatullah
Fitriani, V. 2003. Ekstraksi dan Karakterisasi Pektin dari Kulit Jeruk Lemon
(Citrus medica var Lemon). Skripsi. Bogor : IPB.
Garna, H., Mabon, N., Robert, C., Cornet, C., Nott, K., Legros, H., Wathelet, B.,
and Paquot, M. 2007. Effect of Extraction Conditions on The Yield
54
and Purity of Apple Pomace Pectin Precipitated but Not Washed by
Alcohol. J Food Sci. 2007 Jan; 72(1):C001-9.
Goycoolea, F.M. dan Adriana, C. 2003. Pectins from Opuntia Spp. : A Short
Review. J.PACD. 17-29.
Hanum, F., Kaban, I.M.D dan Tarigan, M.A. 2012. Ekstraksi Pektin dari Kulit
Buah Pisang Kepok (Musa paradisiaca). Jurnal Teknik Kimia USU,
Sumatera Utara.
Hariyati, M. 2006. Ekstraksi dan Karakterisasi Pektin dari Limbah Proses
Pengolahan Jeruk Pontianak. Skripsi. Bogor : IPB.
Hart, H., Craine, L. E dan Hart, D.J.. 2003. Kimia Organik. Edisi Kesebelas.
Jakarta : Erlangga.
Hasbullah. 2001. Teknologi Tepat Guna Agroindustri Kecil Sumatera Barat –
Pektin Jeruk. Jakarta : Dewan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan
Industri Sumatera Barat.
Hastuti, B. 2016. Pektin dan Modifikasinya untuk Meningkatkan Karakteristik
Sebagai Adsorben. Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia VIII.
Program Studi Pendidikan FKIP UNS.
Hutagalung, D.P. 2013. Ekstraksi dan Evaluasi Sifat-Sifat Prebiotik Pektin
Kulit Pisang. Skripsi. Jember : Universitas Jember.
IPPA (International Pectins Procedures Association). 2002. What is Pectin.
http://www.ippa.info/history_of_pektin.htm. Diakses pada 14 Agustus
2017.
Ismail, NSM., Ramli, N., Hani, NM., and Meon, Z. 2012. Extraction and
Characterization of Pectin from Dragon Fruit (Hylocereus
Polyrhizus) Using Various Extraction Conditions. Sains Malaysiana,
41: 41-45.
Istiqomah. 2013. Perbandingan Metode Ekstraksi Maserasi Dan Sokletasi
Terhadap Kadar Piperin Buah Cabe Jawa (Piperis retrofracti
fructus). Skripsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
Kader, A. A. 2002. Postharvest Technology Of Horticultura Crops. 3rd ed.
Pub.No. 3311. Oakland : University of California.
Kalapathy, U. dan Proctor, A. 2001. Effect of Acid Extraction and Alcohol
Precipitation Conditions on The Yield and Purity of Soy Hull Pectin.
Food Chemistry 73 : 393 – 396.
Linawati, N.N. 2016. Karakteristik Kimia Pektin Kulit Pisang Embug (Musa
accuminate) dari Hasil Presipitasi Etanol Menggunakan Metode
Sonikasi dan Sentrifugasi. Skripsi. Jember : Universitas Jember
55
Maran, J.P., Sivakumar, V., Thirugnanasambandham, K., and Sridhar, R. 2013.
Optimization of Microwave Assisted Extraction of Pectin From
Orange Peel. Carbohydrate Polymer. 97:703–709.
Maulana, S. 2015. Ekstraksi dan Karakterisasi Pektin dari Limbah Kulit
Pisang Uli. Skripsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
Megawati dan Machsunah, E.L. 2016. Ekstraksi Pektin dari Kulit Pisang
Kepok (Musa paradisiaca) Menggunakan Pelarut HCl sebagai
Edible Film. JBAT 5 (1) (2016) 14-21.
Meilina, H., dan Sailah, I. 2003. Produksi Pektin dari Kulit Jeruk Lemon
(Citrus medica). Prosidium Simposium Nasional Polimer V
Muhamadzadeh, J., Sadghi-Mahoonak, A.R., Yaghbani, M., Aalam, M. 2010.
Extraction of Pectin from Sunflower Head Residues of Selected
Iranian Caltivers. World Applied Science Journal, 8: 21-24.
Muhidin, D. 1999. Agroindustri Papain dan Pektin. Jakarta : Penebar
Swadaya.
Mukhriani. 2014. Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa
Aktif. Jurnal Kesehatan Volume VII No. 2/2014
Munadjim. 1988. Teknologi Pengolahan Pisang. Jakarta : Gramedia
Nelson, D.B dan Wiles, R.L. 1977. Comercially Important Pectic Subtances.
Didalam H.D. Graham (ed) Food Colloids. AVI Publishing Inc.,
Westport
Ningsih, D.M. 2009. Ekstraksi dan Karakterisasi Pektin dari Limbah Kulit
Buah Pepaya (Carica papaya L.). Skripsi. Malang : Universitas
Brawijaya
Nurhayati, N., Maryanto, M., dan Tafrikhah, R. 2016. Ekstraksi Pektin dari Kulit
dan Tandan Pisang dengan Variasi Suhu dan Metode. Agritech, Vol.
36, No. 3, Agustus 2016.
Nurhikmat, A. 2003. Ekstraksi Pektin dari Apel Lokal : Optimalisasi pH dan
Waktu Hidrolisis. Yogyakarta : Balai Pengembangan Proses dan
Teknologi Kimia – LIPI
Nurviani., Bahri, S., dan Sumarni, N.K. 2014. Ekstraksi dan Karakterisasi
Pektin Kulit Buah Pepaya Varietas Cibinong, Jinggo dan
Semangka. Online Jurnal of Natural Science, Vol.3(3): 322 – 330.
Patil, A.G., Patil, D.A., Phatak, A.V. and Chandra, N. 2010.. Physical And
Chemical Characteristics Of Carambola (Averrhoa carambola L)
Fruit at Three Stages Of Maturity. International Journal of Applied
Biology and Pharmaceutical Technology, 1(2), 624-629
56
Perina, I., Satiruiani., Soetaredjo, F.E., dan Hindarso, H. 2007. Ekstraksi Pektin
dari Berbagai Macam Kulit Jeruk. WIDYA TEKNIK Vol. 6 No. 1, 2007
(1-10).
Piknik, W., and Voragen A.G.J. 1992. Pectin Substances and Other Uronides.
The Biochemistry of Fruits and Their Product, Volume I, 53-87
Prabawati, S., Suyanti., dan Setyabudi, D. A. 2008. Teknologi Pascapanen dan
Teknik Pengolahan Buah Pisang. Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Pascapanen Pertanian.
Pratiwi, E. 2010. Perbandingan Metode Maserasi, Remaserasi, Perkolasi dan
Reperkolasi dalam Ekstraksi Senyawa Aktif Andrographolide dari
Tanaman Sambiloto (Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees). Skripsi.
Bogor : IPB.
Promosiana, A dan Atmojo, H.D. 2014. Statistik Produksi Holtikultura Tahun
2014. Jakarta. http://hortikultura.pertanian.go.id/wp-
content/uploads/2016/02/Statistik-Produksi-2014.pdf . Diakses pada 14
Agustus 2017.
Puspitasari, A.D., dan Proyogo, L.S. 2016. Perbandingan Metode Ekstraksi
Maserasi dan Sokletasi terhadap Kadar Fenolik Total Ekstrak
Etanol Daun Kersen (Muntingia calabura). Semarang : Universitas
Wahid Hasyim
Raji, Z., Khodaiyan, F., Rezaei, K., Kiani, H., and Hosseini, S.S.. 2016.
Extraction Optimization and Physicochemical Properties of Pectin
from Melon Peel. International Journal of Biological Macromolecules
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.01.146
Ramli, N., dan Asmawati. 2011. Effect of ammonium oxalateand acetic acid
at several extraction time and pH on some physicochemical
properties of pectin from cocoa husk (Theobroma cacao). African
journal of Food Science, 5:790-798.
Ranggana, S. 2000. Handbook of Analysis and Quality Control for Fruit and
Vegetable Product, Second Edition.
Rao, M., & Silva, J. L. 2006. Pectins: Structure, Functionality, and Uses. In A.
M. Stephen, G. O. Phillips, & P. A. Williams (Eds.), Food
Polysaccharides and Their Applications. Boca Raton, Florida: CRC
Press.
Redgwell, RJ., MacRae, E., Hallett, I., Fischer, M., Perry, J., and Harker, R.
1997. In Vivo and In Vitro Swelling of Cell Walls During Fruit
Ripening Planta. 203: 162-173.
57
Rha, H.J., Bae, I.Y., Lee, S., Yoo, S.H., Chang, P.S., Lee, H.G. 2011.
Enhancement of Anti-Radical Activity of Pectin from Apple Pomace
by Hydroxamation. Food Hydrocolloids, 25: 545–548.
Ristianingsih, Y., Nata, I.F., Anshori, D.S., dan Putra I.P.A. 2014. Pengaruh
Konsentrasi HCl Dan Ph pada Ekstraksi Pektin dari Albedo Durian
dan Aplikasinya pada Proses Pengentalan Karet. Konversi, Volume 3
No. 1, April 2014.
Roikah, S., Rengga, W.D.P., Latifah dan Kusumastuti, E. 2016. Ekstraksi dan
Karakterisasi Pektin dari Belimbing Wuluh (Averrhoa Bilimbi,L).
JBAT 5 (1) (2016) 29-36.
Rouse, A.H., 1977. Pectin : Distribution, Significance didalam S. Nagy, P.E
Shaw dan V.E Velhdhuis (eds) Citrus Science and Technology Vol I.
AVI Publ. Co., Connecticut
Sirisakulwat, S., Nagel, A., Sruamsiri, P., Carle, R., and Neidhart, S. 2008. Yield
and Quality of Pectins Extractable From The Peels of Thai Mango
Cultivars Depending on Fruit Ripeness. Journal of Agricultural Food
Chemistry, 56: 10727–10738
Sirotek, K., Slovakova, L., Kopecny, J., and Marounek, M. 2004. Fermentation
of Pectin and Glucose, and Activity of Pectindegrading Enzymes in
The Rabbit Caecal Bacterium Bacteroides Caccae. Letters in Applied
Microbiology(38), 327–332.
Soltani, M., Alimardani, R., and Omid, M. 2010. Prediction of Banana Quality
During Ripening Stage Using Capacitance Sensing System. AJCS
4(6):443-447
Subagyo, P., dan Achmad, Z. 2010. Pemungutan Pektin dari Kulit dan Ampas
Apel Secara Ekstraksi. EKSERGI Volume X, Nomor 2
Sulihono, A., Tarihoran, B. dan Agustina, T.E. 2012. Pengaruh Waktu,
Temperatur, dan Jenis Pelarut Terhadap Ekstraksi Pektin dari Kulit
Jeruk Bali (Citrus maxima). Jurnal Teknik Kimia No. 4, Vol. 18,
Desember 2012.
Sunandar, A., Sumarsono, R.B., Benty, D.D.N., dan Nurjanah, N. 2017. Aneka
Olahan Pisang Sebagai Upaya Meningkatkan Nilai Jual Pisang dan
Pendapatan Masyarakat. ABDIMAS PEDAGOGI, VOLUME 1 NOMOR
1: 8-15
Sundar, RAA., Rubila, S., Jayabalan, R., and Ranganathan TV. 2012. A Review
on Pectin: Chemistry Due to General Properties of Pectin and
Pharmaceutical Uses. Scientific eports, 1: 2, 1-4.
58
Suparmi dan Prasetya, H. 2013. Aktifitas Antioksidan Ekstrak Kasar Pigmen
Karotenoid pada Kulit Pisang Ambon Kuning (Musa parasidiaca
sapientum): Potensi sebagai Suplemen Vitamin A. Jurnal Sains
Media Vol 4, No 1.
Susanto, W. H. 1999. Teknologi Minyak dan Lemak Pangan. Malang :
Universitas Brawijaya.
Susilowati., Munandar, S., Edahwati, L., dan Harsini, T. 2013. Ekstraksi Pektin
dari Kulit Buah Coklat dengan Pelarut Asam Sitrat. Volume 11,
Nomor 1
Sutanto, A dan Edison, H.S,. 2005. Diskripsi Pisang Indonesia. Balai Penelitian
Tanaman Buah
Tchobanoglous, G., Theisen, H and Vigil, S. 2003. Integrated Solid Waste
Management: Engineering Principles and Management Issues. New
York : McGraw-Hill.
Tuhuloula, A., Budiyarti, L.dan Fitriana, E.N. 2013. Karakterisasi Pektin
dengan Memanfaatkan Limbah Kulit Pisang Menggunakan Metode
Ekstraksi. Konversi, Volume 2 No. 1. Universitas Lambung Mangkurat.
Wijaksono, P.A. 2016. Karakterisasi Pektin Hasil Ekstraksi Kulit Buah Jeruk
Manis (Citrum aurantium L) dengan Variasi Pelarut. Akademi Analis
Farmasi dan Makanan.
Willat, W.G.T., Knox, J.P. dan Mikkelsen, J.D. 2006. Pectin : New Insights Into
on Old Polymer are Starting to Gel. Trends in Food Science and
Technology 17: 97-1004.
Winarno, F.G. 2004. Kimia Pangan dan Gizi. Jakarta : Gramedia