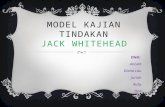Kajian Genealogi-Arkeologis Terhadap Candi Borobudur
Transcript of Kajian Genealogi-Arkeologis Terhadap Candi Borobudur
MAKALAH KELOMPOK HYBRID
FILSAFAT DAN METODOLOGI DALAM HUBUNGAN
INTERNASIONAL
“Kajian Genealogi-Arkeologis Terhadap Candi Borobudur”
Ketua Kelompok:
Fahrul Firmansyah 170210100023
Anggota:
Floranesia lantang 170210100007
Annisa Handayani 170210100095
Putri Gita Ansani 170210100041
Nike Ariesti 170210100062
Luh Putu Raditya 170210100009
Anike Pratiwi 170210100051
Tamia Tirta A. 170210100057
Annisa Sanna Nikita 170210100065
Aghnia Chasya 170210100097
Denna Estianti 170210100063
Rian Hernamawan 170210100019
Yoga Restu Nugraha 170210100091
Bobby Muhammad Ihsan 170210100089
Moehammad Khahfi 170210100036
Deden Habibi 170210100122
Sulthan Fajri Majid 170210100072
Dimas Rimo Triadji 170210100100
Anissa Chandradiva 170210100014
Mufti Aditya 170210100080
M. Rangga Bisma 170210100061
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2013
- 1 -
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia mempunyai kekayaan budaya yang beragam dan salah satunya adalah
candi. Terdapat kurang lebih 38 candi yang telah diketahui dan candi lainnya yang
sampai saat ini belum mempunyai nama. Candi mempunyai nilai-nilai filosofis tinggi
yang tersurat maupun tersirat melalui relief-relief yang terukir di batu-batu candi.Candi
membuktikan sebuah peradaban agung yang pernah ada pada masa kerajaan yang
berkuasa di Indonesia terutama saat berjaya serta menyebarnya agama Hindu dan
Budha.
Candi Pendharmaan adalah suatu istilah dalam arkeologi Hindu-Buddha
Indonesia untuk menyebutkan suatu bangunan suci --umumnya candi-- yang didirikan
untuk memuliakan seorang tokoh yang telah meninggal.Kata dharma berasal dari
bahasa Sansekerta yang artinya cukup luas, seperti hukum, aturan hidup dan tingkah
laku yang ditentukan oleh agama dan adat, keadilan, kabajikan, ajaran agama,
kebenaran, kewajiban, kesucian, dan lain-lain.Salah satu pengertian kata dharma dalam
bahasa Jawa kuna adalah lembaga keagamaan, candi, biara, pertapaan, dan bangunan
suci lainnya.
Dalam beberapa karya sastra Jawa Kuna seperti Wirataparwa, Nagarakrtagama
dan Siwaratrikalpa begitupun dalam karya sastra lainnya seperti Pararaton dan Kidung
- 2 -
Harsyawijaya banyak disebutkan kata dharma atau dhinarma yang artinya membangun
candi untuk tokoh tertentu. Dengan demikian kata pendharmaan adalah bentukan kata
dalam Bahasa Indonesia dengan awalan pe dan akhiran an dengan kata dasar kata Jawa
Kuna dharma, maka artinya dapat menunjukkan lokasi atau tempat suatu bangunan suci
tertentu atau bangunan suci itu sendiri. Selanjutnya yang akan ditinjau dalam bahasan
ini adalah beberapa nama pendharmaan di wilayah Jawa bagian timur yang berhasil
disesuaikan dengan berita dalam karya sastra, serta akan diungkap pula beberapa
pendharmaan bagi tokoh-tokoh penting yang masih belum dapat diketahui
keberadaannya hingga sekarang.
Candi-candi Hindu di Indonesia umumnya dibangun oleh para raja pada masa
hidupnya. Arca dewa, seperti Dewa Wishnu, Dewa Brahma, Dewi Tara, Dewi Durga,
yang ditempatkan dalam candi banyak yang dibuat sebagai perwujudan leluhurnya.
Bahkan kadang-kadang sejarah raja yang bersangkutan dicantumkan dalam prasasti
persembahan candi tersebut.Berbeda dengan candi-candi Hindu, candi-candi Buddha
umumnya dibangun sebagai bentuk pengabdian kepada agama dan untuk mendapatkan
ganjaran.Ajaran Buddha yang tercermin pada candi-candi di Jawa Tengah adalah
Buddha Mahayana, yang masih dianut oleh umat Buddha di Indonesia sampai saat ini.
Berbeda dengan aliran Buddha Hinayana yang dianut di Myanmar dan Thailand (PNRI,
2013).
Karena ajaran Hindu dan Buddha berasal dari negara India, maka bangunan
candi banyak mendapat pengaruh India dalam berbagai aspeknya, seperti: teknik
bangunan, gaya arsitektur, hiasan, dan sebagainya. Walaupun demikian, pengaruh
kebudayaan dan kondisi alam setempat sangat kuat, sehingga arsitektur candi Indonesia
- 3 -
mempunyai karakter tersendiri, baik dalam penggunaan bahan, teknik kontruksi maupun
corak dekorasinya
Salah satu candi yang terkenal di Indonesia bahkan di dunia adalah candi
borobudur. Candi ini merupakan monumen Budha terbesar di dunia.Dibangun pada
masa Raja Samaratungga dari Wangsa Syailendra pada tahun 824. Candi Borobudur
dibangun 300 tahun sebelum Angkor Wat di Kamboja dan 400 tahun sebelum katedral-
katedral agung di Eropa (Indonesia Travel, 2013). Arkeologi sangat membantu dalam
menelusuri lebih lanjut karya-karya sastra yang dimaknai oleh candi sehingga
menghidupkan seni yang bukan hanya material atau tumpukan batu tetapi nilai-nilai
sakral serta makna ketika peradaban tersebut pernah ada.Hubungan antara masyarakat
dengan Tuhan ataupun Dewa, pengelompokkan kelas manusia, serta sesuatu yang
dianggap suci yang dipahat di batu-batu candi.
Arkeologi dalam hal ini, yaitu Arkeologi pengetahuan yang melihat sisi tangible
dan intangible dari candi sebagai peninggalan. Sebuah kejayaan masa peradaban
lampau yang masih eksis hingga saat ini dalam bentuk peninggalan yaitu candi,
memberikan ruang leluasa untuk diteliti tidak hanya dari sisi kebudayaan, tetapi makna-
makna tersirat saat peradaban tersebut ada, dan keterkaitan antara eksistensi peradaban
tersebut dengan masa sekarang sehingga memunculkan jawaban atas relasi antara kedua
bagian ini. Ide-ide yang dimunculkan dalam proses mendokumentasikan candi hingga
pergantian dokumentasi dari zaman saat peradaban tersebut eksis hingga masa sekarang.
Lebih lanjut melihat bagaimana peradaban tersebut dianggap ada dan menjadi wacana
internasional yang dimunculkan melalui konsep ―power-knowledge‖ dimana
- 4 -
pengetahuan yang menjadi suatu realitas sosial berasal dari kekuasaan dan tidak pernah
lepas dari kekuasaan.
1.2 Identifikasi Masalah
Apa Ide dibalik pembuatan candi Borobudur?
Bagaimana cara mendokumentasikan candi Borobudur?
Apa saja ide-ide masa lalu dari pembangunan Borobudur dan keterkaitannya
dengan masa sekarang?
Mengapa Candi Bodobudur sebagai sebuah artefak yang menyimpan banyak
sejarah masa lalu dianggap dalam HI?
1.3 Tujuan
Makalah penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menerapkan arkeologis
sebagai sebuah metode dalam kaitannya dengan pengetahuan yang berkaitan dengan
nusantara khususnya dalam konteks keagamaan melalui candi Borobudur.
1.4 Manfaat
Makalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan bertambahnya
pengetahuan dan pemahaman mengenai arkeologis itu sendiri serta kaitannya dengan
genealogi secara umum melalui studi kasus yakni candi Borobudur. Makalah ini juga
mencoba menyajikan pemahaman Geneaologi Arkeologi yang dikemukakan Foucault
melalui Candi Borobudur sebagai objek penelitiannya.
- 5 -
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Arkeologi
Foucault secara eksplisit mengenalkan istilah ―arkeologi‖ dalam karyanya The
Order of Things. Tiga tahun kemudian, pada 1969, ia menerbitkan The Archaeology of
Knowledge yang mengenalkan arkeologi sebagai suatu metode. Premis dari metode
arkeologi adalah bahwa sistem pemikiran dan pengetahuan (epistemes atau formasi
diskursif, dalam terminologi Foucault) tersebut diatur oleh aturan, yang di luar tata
bahasa dan logika, yang beroperasi di bawah kesadaran subyek individu dan
menetapkan sistem kemungkinan konseptual yang menentukan batas-batas pemikiran
dalam domain yang diberikan pada periode tertentu (Gutting, 2013).
Penggunaan istilah arkeologi membantu untuk membedakan karya historis dari
sejarah mainstream. Singkatnya, sejarah mainstream membujur (longitudinal): mereka
mempelajari perkembangan sesuatu selama satu periode waktu. Sebaliknya, arkeologi
adalah cross-sectional: ia mempelajari banyak hal yang berbeda yang terjadi pada
waktu yang sama (Museum of Knowledge, 2012).
Arkeologi mempelajari artefak dari satu waktu: tembikar, bahan, buku,
instrumen, dan karya seni bangunan dari strata tertentu. Arkeologi mencoba untuk
memahami bagaimana semua orang berbagai artefak cocok bersama. Pendekatan
arkeologi Foucault terhadap sejarah juga serupa. Dia menelaah beberapa hal yang
berbeda yang terjadi pada waktu yang sama. Sebagai contoh, ia mempelajari artefak
- 6 -
linguistik abad kedelapan belas Eropa, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Kemudian ia
mencoba untuk mencari tahu bagaimana artefak-artefak tersebut saling berhubungan
secara rasional (Museum of Knowledge, 2012).
Arkeologi mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam satu waktu
sejarah tertentu. Ketika ia melakukan penelitian arkeologi, Foucault terutama tertarik
pada pengetahuan, dan ia menggunakan episteme sebagai istilah untuk mengacu ke
sistem pengetahuan pada waktu tertentu. Episteme adalah pola yang dapat dilihat di
berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi , linguistik , dan ilmu pengetahuan . Sebuah
episteme membentuk dasar untuk membedakan pengetahuan sejati dari pengetahuan
palsu. Dengan kata lain, episteme adalah cara spesifik yang bersifat historis dalam
proses ―mengetahui‖ (Museum of Knowledge, 2012).
Singkatnya, arkeologi adalah studi cross-section artefak dalam waktu tertentu.
Hal ini tidak seperti sejarah mainstream karena itu menganalisis berbagai artefak dalam
periode satu waktu daripada melacak perkembangan satu hal selama bertahun-tahun
(Museum of Knowledge, 2012).
2.2 Genealogi-Arkeologis
Pencetus pendekatan Genealogi-Arkeologi adalah Michel Foucault. Dalam
memperkuat pendekatan arkeologi, Foucault menggunakan salah satu metodologi
penelitian Genealogi, yang secara umum dapat diartikan sebagai silisilah. Melalui
silsilah ini kita dapat mengetahui alur sejarah suatu fenomena, ilmu pengetahuan, benda
peninggalan yang ada saat ini. Pendekatan genealogi ini mirip dengan dengan
pendekatan sejarah karena menelusuri suatu sejarah untuk dapat mengetahui. Genealogi
- 7 -
juga bisa dikatakan sebagai ways of knowing, cara mengetahui yang dimaksudkan disini
adalah mengatahui sesuatu melalui mediasi sejarah dan peradaban untuk sampai ke
akarnya.
Foucault menulis mengenai fase arkeologi dalam pendekatan genealoginya.
Dalam tulisannya yang berjudul Archeology of Knowledge, Foucault lebih menekankan
pada suatu peristiwa diskursif dalam analisisnya, dia mendefinisikan Arkeologi sebagai
"yang menggambarkan wacana sebagai praktik‖. Istilah 'Arkeologi' digunakan oleh
Foucault selama tahun 1960 untuk menggambarkan pendekatan untuk menulis sejarah.
Arkeologi adalah tentang memeriksa jejak diskursif dan pesan yang ditinggalkan oleh
masa lalu untuk menulis sejarah masa kini. Dengan kata lain arkeologi adalah tentang
melihat sejarah sebagai cara untuk memahami proses yang telah menyebabkan apa yang
ada hari ini.
Foucault terkenal juga dengan konsepnya tentang relasi antara kekuasaan dan
pengetahuan. Kekuasaan berada dimana-mana, termasuk dalam setiap pengetahuan
yang kita ketahui. Lebih lanjut lagi, dalam metode penelitiannya,yaitu arkeologi,
Foucault berusaha untuk melacak elemen-elemen kekuasaan pembentuk sejarah, bukan
pada sejarahnya melainkan lebih kepada cara-cara pendokumentasian sejarah tersebut.
menurut Foucault, kuasa atau kekausaan itu tersebar dimana-mana. Tidak hanya berada
di pihak penguasa atau pemerintah, kekuasaan juga bisa ada di pihak yang dikuasai.
Contohnya seperti demonstrasi yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah yang
berhasil menggulingkan rezim otoriter. Hal itu cukup menunjukkan bahwa kuasa biasa
berpindah seketika dari pemerintah ke tangan rakyatnya. Bagi Foucault, power atau
kuasa ini juga bersifat produktif, maksudnya adalah kekuasaan atau kuasai ini akan
- 8 -
selalu merangsang munculnya pengetahuan baru. Kuasa menemukan bentuknya dalam
pengetahuan, jika suatu pengetahuan itu digunakan dan diakui oleh banyak orang,
berarti pengetahuan tersebut memiliki kuasa akan orang-orang yang mempercayainya.
Selain bersifat produktif, apa yang dibahas Foucault dalam genealogi
arkeologinya mengenai hubungan antara Kuasa Pengetahuan (Power Knowlegde) juga
bersifat menyebar (Spread). Menurut Foucault suatu diskursif atau pengetahuan tidak
akan pernah bisa dibatasi, relasi antara kekausaan dan pengetahuan akan terus berjalan
untuk menguasai dan mengontrol kehendak orang-orang yang mempercayai atau
meyakini suatu pengetahuan yang sebetulnya telah berkuasa atas kehendak seseorang.
melacak elemen pembentuk sejarah dengan menyelidiki peristiwa-peristiwa
(formasi) diskursif, pernyataan-pernyataan yang dibicarakan dan dituliskan dalam
sebuah konteks sejarah. Pada langkah selanjutnya kita perlu membedakan antara
arkeologi pengetahuan dengan sejarah pemikiran. Pada dasarnya ada empat prinsip yang
membedakan kedua hal tersebut, yakni (George Ritzer, 2003:72):
a) Arkeologi tidak mengupas tentang pemikiran, representasi, yang tersembunyi
atau tampak dalam diskursus. Arkeologi lebih membahas diskursus itu sendiri
sebagai praktik yang menuruti kaidah dan aturannya sendiri.
b) Arkeologi tidak berusaha mencari korelasi linier atau gradual antar diskursus
antar diskursus, tapi berusaha mencari dan melihat kekhasan dari diskursus itu
sendiri.
c) Arkeologi tidak membahas kajian tentang individu atau ouveres. Arkeologi
menitikberatkan pada tipe-tipe aturan praktek diskursif yang berkaitan langsung
- 9 -
dengan ouvere-ouvere individu. Oleh sebab itu arkeologi menolak kehadiran
author sebagai bagian dari kesatuan kajian.
d) Arkeologi tidak menyelidiki kelahiran diskursus tapi lebih pada detesis
sistematik sebagai sebuah objek diskursus (George Ritzer, 2003:72).
2.3 Candi Borobudur
Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur,
Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah. Secara astronomis terletak di 7° 36' 28''
LS dan 110° 12' 13'' BT. Lingkungan geografis Candi Borobudur dikelilingi oleh
Gunung Merapi dan Merbabu di sebelah Timur, Gunung Sindoro dan Sumbing di
sebelah Utara, dan pegunungan Menoreh di sebelah Selatan, serta terletak di antara
Sungai Progo dan Elo. Candi Borobudur didirikan di atas bukit yang telah dimodifikasi,
dengan ketinggian 265 dpl. Pada akhir abad ke VIII, Raja Samaratungga dari Wangsa
Syailendra lantas Candi Borobudur yang dipimpin arsitek bernama Gunadharma
hinggga selesainya tahun 746 Saka atau 824 Masehi (Balai Konservasi Borobudur,
2011).
Mengenai penamaannya juga terdapat beberapa pendapat diantaranya:
Menurut Raffles: Budur yang kuno (Boro= kuno, budur= nama tempat) Sang Budha
yang agung (Boro= agung, budur= Buddha) Budha yang banyak (Boro= banyak, budur=
Buddha). Menurut Moens: Kota para penjunjung tinggi Sang Budha. Menurut Casparis:
Berasal dari kata sang kamulan ibhumisambharabudara, berdasarkan kutipan dari
prasasti Sri Kahulunan 842 M yang artinya bangunan suci yang melambangkan
kumpulan kebaikan dari kesepuluh tingkatan Bodhisattva. Menurut Poerbatjaraka: Biara
di Budur (Budur= nama tempat/desa). Menurut Soekmono dan Stutertheim: Bara dan
- 10 -
budur berarti biara di atas bukit Menurut Soekmono fungsi Candi Borobudur sebagai
tempat ziarah untuk memuliakan agama Budha aliran Mahayana dan pemujaan nenek
moyang (Balai Konservasi Borobudur, 2011).
Pada dasarnya Borobudur merupakan piramid dua tingkat yang menggambarkan
sepuluh tingkatan dari sistem kosmik Budha Mahayana.
Gambar 1.1 Susunan Candi Borobudur
(sumber: http://www.teruskan.com/7172/makna-3-susunan-candi-borobudur.html)
Di bagian paling bawah candi disebut Kamadhatu, salah satu nafsu duniawi.
Selanjutnya ada lima tingkat yang semakin ke atas berukuran semakin kecil, kelima
tingkat ini disebut Rupadhatu. Di atas Rupadhatu terdapat tiga tingkat berbentuk
lingkaran yang membentuk Arupadhatu, yang merupakan tingkatan di mana seseorang
mencapai kehidupan yang lebih baik dan bebas dari ikatan duniawi. Puncak Borobudur
dimahkotai oleh stupa besar tertutup yang dibangun di atas dua kuntum teratai yang
sedang mekar.Dinding-dinding yang terdapat pada tingkat berbentuk persegi dihiasi
ukiran yang indah menggambarkan kisah kehidupan, reinkarnasi dan pencapaian akhir
- 11 -
tentang kebenaran ajaran Budha, ditambah dengan ratusan gambar Budha dalam
berbagai perwujudannya yang menghiasi dinding-dinding. Tingkatan lingkaran yang
paling atas melambangkan keabadian dan keadaan tanpa awal dan akhir.
Di tingkat paling atas ini dijelaskan bahwa tingkat tertinggi ajaran Budha adalah
mengajarkan hukum sebab-akibat yang disebut dengan "karma". Dari sekian banyak
patung, hanya dua di antaranya yang berada dalam stupa terbuka. Satu di antaranya
terlihat hanya sebagian kepalanya, yang lain kelihatan utuh dengan tangan santai
dibelakang sambil menatap lurus gemerlapnya gunung di kejauhan, seolah-olah
mengajarkan bahwa hidup penuh penderitaan. Penderitaan itu disebabkan oleh hawa
nafsu.Hawa nafsu dapat dikendalikan dengan meditasi.Hidup dapat dikendalikan
dengan berbuat baik.Hanya Budha yang dapat menunjukkan jalan menuju keselamatan
yang disebut ―Nirvana‖. ketika Dengan mengunjungi Borobudur dan mengamati 27.000
gambaran dan ukiran mengenai ajaran Budha pada sekeliling candi, seolah-olah kita
sedang melakukan perjalanan religius (Taste of Jogja, 2013).
2.4 Ajaran Buddha
Agama Buddha merupakan agama Kedua yang masuk ke Indonesia, bersamaan
dengan masuknya Agama Hindu yang di bawa oleh pedagang dari india. Dimana
didalam ajarannya agama Buddha ini memiliki Sang Buddha sebagai yang tertinggi dan
maha Penciptanya. Dimana Tentunya di dalam ajaran agama Buddha ini, diketahui akan
adanya ajaran Karma Phalla seperti yang terdapat di dalam ajaran Agama hindu sebab
pada dasarnya agama Buddha berasal dari Agama Hindu sendiri.
- 12 -
Baik di dalam agama Hindu maupun Buddha, keduanya memiliki 3 hal utama
dalam ajarannya, yang mengajarkan diharuskannya adanya keselarasan di dalam
kehidupan. Alam semesta ini terbagi atas, tengah dan bawah dan di dunia ini, dunia itu
terbagi menjadi alam dimana Kesucian atau Nirwana, Alam dimana sudah mulai
terdapat kesucian dan pelepasan terhadap hawa nafsu dan Alam Manusia yang berada di
bawah yakni penuh hawa nafsu. Di dalam hindu terkenal dengan Bhur, Bvah, Svah dan
di dalam Buddha terkenal dengan alam semesta yang menurut ajaran Buddha terdiri atas
3 bagian besar, yaitu:
a) Kamadhatu
Kamadhatu, yaitu dunia yang masih dikuasai oleh kama atau nafsu (keinginan)
yang rendah, yaitu dunia manusia biasa seperti dunia kita ini.
b) Rupadhatu
Rupadhatu, yaitu dunia yang sudah dapat membebaskan diri dari ikatan nafsu,
tetapi maish terikat oleh rupa dan bentuk, yaitu dunianya orang suci dan
merupakan ―alam antara‖ yang memisahkan ―alam bawah‖ (kamadhatu) dengan
―alam atas‖ (arupadhatu).
c) Arupadhatu.
Arupadhatu, yaitu ―alam atas‖ atau nirwana, tempat para Buddha bersemayam,
dimana kebebasan mutlak telah tercapai, bebas dari keinginan dan bebas dari
ikatan bentuk dan rupa (Karaton Surakarta, 2013).
- 13 -
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Cara Mendokumentasikan Candi Borobudur
3.1.1 Mpu Prapanca
Dalam dokumentasi Borobudur ―Nagarakertagama‖ merupakan Satu-satunya
naskah Jawa kuno yang memberi petunjuk mengenai adanya bangunan suci Buddha
yang mungkin merujuk pada Borobudur. Ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365.
Mpu Prapanca dalam Negarakertagama.
Negarakertagama atau Nagarakertagama merupakan satu-satunya litearatur kuno
yang menyebutkan mengenai Candi Borobudur (Moens, 2007). Moens dalam laporan
penelitiannya tersebut menyebutkan bahwa masih terdapat perdebatan antara para
peneliti dan ahli mengenai Candi Borobudur sehingga dalam makalah ini diputuskan
bahwa Negarakertagama yang dikarang oleh Mpu Prapanca sebagai sebuah sumber
artefak metode pendokumentasian di masa kerajaan Hindu-Budha di kawasan sekitar
candi.
Berbagai sumber telah menyebutkan bahwa Candi Borobudur di dirikan pada
masa kerajaan Mataram Kuno di bawah pemerintahan wangsa Syailendra (PBS, 2013).
Dalam sumber yang sama disebutkan pula bahwa arsitek dari Candi Borobudur adalah
Gunadarma. Cukup sulit untuk menemukan bagaimana maharaja dari wangsa syailendra
pada mulanya membangun Candi Borobudur, dalam laporan penelitian oleh Moens
disebutkan bahwa dalam Negarakertagaman muncul nama Borobudur namun bukan
- 14 -
dikaitkan dengan maharaja Syailendra dan penggagas pendiriannya melainkan lebih
kepada deskripsi keberadaan secara fisik.
Penyusun menganalisis dari berbagai sumber yang ada termasuk laporan
penelitian Moens dan menyimpulkan bahwa pendirian Candi Borobudur oleh maharaja
Syailendra di masa itu lebih mengarah kepada pembangunan sebuah tempat ibadah yang
memadai bagi masyarakat yang beragama Budha.
3.1.2 Sir Thomas Stamford Raffles
Setelah keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha, Candi Borobudur baru ditemukan
kembali pada tahun 1814, oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Ketika ia datang untuk
memeriksa kemajuan ekspedisinya di Indonesia, ia menemukan sebuah piramida kolosal
dimana ketika naik ke puncak akan berbentuk lonceng besar. Raffles yang suka
mengeksplorasi berbagai daerah pada awalnya berusaha untuk mengeksplorasi daerah
gunung berapi yang ada di daerah Kedu. Namun, ketika Raffles beserta pasukannya
berusaha untuk menemukan gunung legendaris yang ada di sana, justru menemukan
sebuah bangunan yang terpendam di dalam puing-puing (PBS, 2013).
Kemudian Raffles berusaha untuk membersihkan puing-puing bangunan yang
ditemukannya, dan akhirnya menemukan bangunan yang berukir relief-relief. Raffles
yang memiliki ketertarikan akan hal tesebut kemudian berusaha untuk
mendokumentasikan keberadaan Candi Borobudur di dalam buku ―The History of
Java‖. Karena catatan sejarah kurang memadai, Raffles tidak dapat menentukan tanggal
yang tepat mengenai konstruksi Borobudur, tapi ia memang memiliki beberapa
wawasan dalam tujuan struktur: ―Kemiripan gambar yang mengelilingi monumen ini
- 15 -
mengacu pada sosok Buddha, yang telah memperkenalkan pendapat bahwa Borobudur
eksklusif terbatas untuk menyembah Buddha‖.
Raffles berperan besar dalam restorasi candi pada saat itu yang masih tertimbun
oleh tanah dan semak. Ia mengirim seorang arkeologis belanda bernama H.C. Cornelius
untuk meneliti candi. Cornelius dan para pekerja melakukan restorasi dalam jangka
waktu dua bulan. Pekerjaan yang dilakukan oleh Cornelius ini dilaporkan dalam buku
Raffles berjudul "The History of Java" yang diterbitkan pada tahun 1817.
Kemudian, pada tahun 1835, struktur dan dimensi dasar Borobudur pertama kali
diselidiki oleh Hartmann, dan seniman Jerman, A. Shaefer, membuat foto pertama
―Daguerreotype‖ (proses pertama fotografi praktis yang menggunakan kamera obscura
(alat bantu menggambar bagi para seniman yang setelah kelahiran fotografi dikenal
sebagai kamera foto) (Atmadi, 1998).
Di antara buku-buku pada abad ke-19 di Indonesia yang diterbitkan di Inggris,
The History of Java memegang posisi yang unik. Ketika menjabat sebagai Letnan
Gubernur di Indonesia, termotivasi oleh kekagumannya akan sejarah, cerita-cerita
eksotis, bangunan arsitektur dan budaya Indonesia, Raffles melakukan pencarian besar
dalam mendokumentasikan sejarah pulau, budaya, arsitektur dan peradaban
kontemporer Indonesia khusunya Jawa. Sejarah Raffles tentang Jawa sampai hari ini
dianggap sebagai sebuah karya yang sangat penting, terutama karena akurasi yang
dirasakan dalam mendokumentasikannya.
3.1.3 C. Leemans dan JFG Brumund
F.C. Wilsen, seorang insinyur pejabat Belanda bidang teknik, mempelajari
monumen ini dan menggambar ratusan sketsa relief. Peneliti lain J.F.G. Brumund juga
- 16 -
melakukan penelitian lebih terperinci atas monumen ini, yang dirampungkannya pada
1859. Saat itu pemerintah belanda berencana menerbitkan artikel berdasarkan penelitian
Brumund yang dilengkapi sketsa-sketsa karya Wilsen, tetapi Brumund menolak untuk
bekerja sama. Pemerintah kemudian menugaskan ilmuwan lain, C. Leemans, yang
mengkompilasi monografi berdasarkan sumber dari Brumund dan Wilsen. Pada 1873,
monograf pertama dan penelitian lebih detil atas Borobudur diterbitkan dengan judul
The Borobudur Monography (Jacques, 1998).
3.1.4 JW Ijzerman
Pada tahun 1885 Ijzerman melakukan penelitian pada dasar candi dan
menemukan sejumlah relief. Pada tahun-tahun 1890-1891, keseluruhan relief kemudian
dikenal sebagai relief Karmawibhanga dengan sejumlah 160 panel, dan difoto oleh K.
Kefas setelah bagian dasar ini ditutup lagi. Para ahli menyimpulkan bahwa Borobudur
harus telah dibangun oleh raja-raja Sailendra yang memerintah di Jawa Tengah pada
waktu itu (PBS, 2013).
3.1.5 TH. van Erp dan Nicholas J. Krom
Seiring berjalannya waktu setelah penemuan Borobudur tahun 1814 oleh
colonial British, Pada 1907 sampai 1911, Borobudur mengalami restorasi besar-besaran.
Dengan dipimpin oleh Ir. Th. Van Erp, seorang insinyur Belanda dimana ia tertarik akan
falsafah dan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Borobudur. Untuk itu, Van Erp
mencoba melakukan studi banding selama beberapa tahun di India hingga akhirnya ia
bisa menggambar sketsa bentuk Candi Borobudur. Sementara itu, kajian mengenai
landasan falsafah dan agama yang ada di balik Borobudur, yakni Mahayana-Yogacara
- 17 -
yang cenderung bercampur dengan aliran Tantrayana-Vajrayana, dilakukan oleh
Stutterheim dan NJ. Krom. Setelah rampung dibangun, Borobudur menjadi pusat
spiritual termegah bagi penganut agama Buddha (Krom, 2005) NJ. Krom dan F.D.K
Bosch berhasil mengidentifikasi banyak teks-teks Buddhis bahwa para pembangun
candi telah menggunakan teks-teks Buddha sebagai sumber inspirasi untuk mengukir
narasi relief monumen. pada dinding dinding terdapat kisah tentang Buddha dari
lahirnya sampai meninggal dan kisah kehidupan ajaran Buddha yang dipahatkan pada
reliefnya (Voute, Caesar. E. L, Mark).
Van Erp sendiri menulis artikel lengkap tentang candi Borobudur, yang baru
diterbitkan pada tahun 1927 dan 1931. Kedua artikel inilah yang paling penting untuk
penelitian tentang candi Borobudur. Kemudian pada tahun 1975, Hariani Santiko dan
Siswadhi mengkompilasi “Annotated Bibliography of Borobudur” yang di ambil dari
laporan penemuan pertama di Borobudur, sampai dengan artikel yang dipublikasikan
pada tahun 1975, yang mencapai hasil yang bagus. Tetapi Annotated Bibliography of
Borobudur belum pernah dipublikasikan (Jagad Kejawen, 2013).
3.1.6 W.O.J. Nieuwenkamp
Spekulasi, teori, maupun pernyataan terus berlanjut tentang bagaimana candi ini
dibangun, salah satunya pada tahun 1931, seniman dan pakar arsitektur Hindu Buddha,
W.O.J. Nieuwenkamp (Krom, 2005) mengajukan teori bahwa daratan Kedu — lokasi
Borobudur menurut legenda Jawa, dulunya adalah sebuah danau purba. Borobudur
dibangun melambangkan bunga teratai yang mengapung di atas permukaan danau.
Namun ini baru sebuah hipotesa yang lalu menjadi perdebatan hangat di kalangan para
ilmuwan saat itu. Menurut Nieuwenkamp, Borobudur dibangun melambangkan bunga
- 18 -
teratai yang mengapung di atas permukaan danau. Bunga teratai baik dalam bentuk
padma (teratai merah), utpala (teratai biru), ataupun kumuda (teratai putih) dapat
ditemukan dalam semua ikonografi seni keagamaan Buddha; seringkali digenggam oleh
Boddhisatwa sebagai laksana (lambang regalia), menjadi alas duduk singgasana Buddha
atau sebagai lapik stupa.Bentuk arsitektur Borobudur sendiri menyerupai bunga teratai,
dan postur Budha di Borobudur melambangkan Sutra Teratai yang kebanyakan ditemui
dalam naskah keagamaan Buddha mahzab Mahayana (aliran Buddha yang kemudian
menyebar ke Asia Timur). Tiga pelataran melingkar di puncak Borobudur juga diduga
melambangkan kelopak bunga teratai.
Akan tetapi teori Nieuwenkamp yang terdengar luar biasa dan fantastis ini banyak
menuai bantahan dari para arkeolog, pada daratan di sekitar monumen ini telah
ditemukan bukti-bukti arkeologi yang membuktikan bahwa kawasan sekitar Borobudur
pada masa pembangunan candi ini adalah daratan kering, bukan dasar danau purba.
Kebenaran dari spekulasi yang diberikan oleh Nieuwenkamp memang belum dapat
dipastikan hingga saat ini, namun ia telah memberikan dokumentasi lain dalam
pendokumentasian Candi Borobudur. Hal ini dikarenakan Nieuwenkamp telah
memberikan visualisasi baru mengenai bentukan awal dari candi tersebut pada sebuah
majalah di Jerman.
3.2 Ide-Ide Masa Lalu yang Tersembunyi dari Candi Borobudur
3.2.1 Masa Kerajaan Syailendra secara singkat
Kerajaan Syailendra merupakan sebah wangsa atau dinasti yang berkuasa di
Sriwijaya pulau Sumatera dan di Jawa Tengah sejak tahun 752 (Rapendik, 2013).
- 19 -
Peninggalan dan manifestasi dari wangsa syailendra ini banyak terdapat di dataran Kedu
tepatnya Jawa Tengah. Terdapat beberapa pemikiran yang mencoba menguasai sejarah
dari adanya kerajaan syailendra di tanah Indonesia, diantaranya adalah pemikiran yang
berlandaskan teori India yang menyebutkan bahwa kerajaan Syailendra ini sebenarnya
berasal dari daratan india yaitu tepatnya di Kalingga (Rapendik, 2013). Terjadi proses
imigrasi yang dilakukan oleh keluarga syailendra karena alasan rasa aman di dataran
India tersebut awalnya keluarga syailendra ini mendiami dataran Palembang yang
kemudian mendiami tanah jawa.
Menurut kuasa teori Funan, kerajaan syailendra yang ada di Indonesia itu berasal
dari Funan (kamboja), dalam bentuk transmigrasi ke pulau jawa dan menjadi penguasa
di Mdam pada abad ke 8, kemudian penguasa Mdam yang ternyata keturunan Funan ini
mengganti namanya menjadi keluarga yang berkembang menjadi sebuah kerajaan yang
berpengaruh di Indonesia. Dan Kuasa lainnya adalah pemikiran dari teori Nusantara
yang melihat bahwa berkembangnya kerajaan syailendra di pulau jawa dan Sumatra itu
berasal asli dari tanah nusantara, yaitu berkembang dari Sumatra kemudian di jawa hal
ini dapat terjadi karena adanya ekspansi kekuasaan sriwijaya melintasi dataran sehingga
Kerajaan Syailendra memiliki kekuasaan di wilayah Sumatra dan Jawa tengah
khususnya.
Di Indonesia nama Syailendra dijumpai di dalam prasasti-prasasti, seperti
prasasti kalasan pada tahun 778 (Rapendik, 2013), pertama kali nama syailendra
muncul, selanjutnya nama syailendra muncul kembali di prasasti kelurak pada tahun
782, dalam prasasti Abhayagiriwihara dari tahun 792 Masehi
(dharmmatuńgadewasyaśailendra), prasasti Sojomerto dari sekitar tahun 700 Masehi
- 20 -
(selendranamah) dan prasasti Kayumwuńan dari tahun 824 Masehi
(śailendrawańśatilaka). Di luar Indonesia nama ini ditemukan dalam prasasti Ligor dari
tahun 775 Masehi dan prasasti Nalanda (Rapendik, 2013).
Terdapat peninggalan kejayaan dari kerajaan Syailenndra di Indonesia sebagai
pendukung dari ketiga pemikiran yang telah membaca proses lahir dan berkembangnya
kerajaan Syailendra, yaitu candi Borobudur. Waktu pembangunan Candi Borobudur
diperkirakan berdasarkan perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup
Karmawibhangga dengan jenis aksara yang lazim digunakan pada prasasti kerajaan
abad ke-8 dan ke-9. Diperkirakan Borobudur dibangun sekitar tahun 800 masehi
(Soekmono, 1978). Kurun waktu ini sesuai dengan kurun antara 760 dan 830 M, masa
puncak kejayaan wangsa Syailendra di Jawa Tengah (Soekmono, 1978).
Pada waktu itu wangsa Syailendra sangat dipengaruhi Kemaharajaan Sriwijaya.
Pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75-100 tahun lebih dan
benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan raja Samaratungga pada tahun 825
(Soekmono, 1978).
Mengenai nama Borobudur sendiri banyak ahli purbakala yang menafsirkannya,
di antaranya Prof. Dr. Poerbotjoroko menerangkan bahwa kata Borobudur berasal dari
dua kata Bhoro dan Budur. Bhoro berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti bihara
atau asrama, sedangkan kata Budur merujuk pada kata yang berasal dari Bali Beduhur
yang berarti di atas. Pendapat ini dikuatkan oleh Prof. Dr. WF. Stutterheim yang
berpendapat bahwa Borobudur berarti Bihara di atas sebuah bukit. Sedangkan Prof. JG.
De Casparis mendasarkan pada Prasasti Karang Tengah yang menyebutkan tahun
pendirian bangunan ini, yaitu Tahun Sangkala: rasa sagara kstidhara, atau tahun Caka
- 21 -
746 (824 Masehi), atau pada masa Wangsa Syailendra yang mengagungkan Dewa
Indra. Dalam prasasti didapatlah nama Bhumisambharabhudhara yang berarti tempat
pemujaan para nenek moyang bagi arwah-arwah leluhurnya. Bagaimana pergeseran kata
itu terjadi menjadi Borobudur? Hal ini terjadi karena faktor pengucapan masyarakat
setempat.
Kedua hal ini menunjukkan fungsi Candi Borobudur ini sendiri di masa Wangsa
Syailendra yaitu sebagai Bihara atau Biara, yaitu tempat keagamaan, yang disebut juga
dalam nama Bhumusambharabhudhara, dimana Candi Borobudur juga difungsikan
sebagai tempat pemujaan arwah nenek moyang atau leluhur, yang apabila dalam adat
istiadat Jawa dianggap spesial, layaknya Dewa.
Adapun periodisasi pembangunan borobudur pada wangsa Syailendra kurang
lebih seperti pada bagan di bawah ini (Paul Michel, 2006: 171):
775—800 Dharanindra
Mataram,
Jawa
Tengah
Prasasti
Kelurak (782), Prasa
ti Ligor B (sekitar
787)
Jugaberkuasa
di Sriwijaya (Sumatera),
membangun Manjusrigrha,
memulai membangun
Borobudur (sekitar 770), Jawa
menyerang dan menaklukan Ligor
dan Kamboja Selatan (Chenla)
(790)
812—833 Samaratungga
Mataram,
Jawa
Prasasti
Karangtengah (824)
Juga berkuasa di Sriwijaya,
merampungkan Borobudur (825)
- 22 -
Tengah
Tabel 3.1 Periodisasi Pembangunan Borobudur
Candi Borobudur dibuat pada masa Wangsa Syailendra yang menganut agama
Buddha, di bawah kepemimpinan Raja Samarotthungga. Arsitektur candi ini dirancang
berdasarkan tuturan seorang tokoh masyarakat pada kala itu yang bernama
Gunadharma. Pembangunan candi itu selesai pada tahun 847 M. Menurut prasasti
Kulrak (784M) pembuatan candi ini dibantu oleh seorang guru dari Ghandadwipa
(Bengalore) bernama Kumaragacya yang sangat dihormati, dan seorang pangeran dari
Kashmir bernama Visvawarman sebagai penasihat yang ahli dalam ajaran Buddis
Tantra Vajrayana. Pembangunan candi ini dimulai pada masa Maha Raja Dananjaya
yang bergelar Sri Sanggramadananjaya, dilanjutkan oleh putranya, Samarotthungga, dan
oleh cucu perempuannya, Dyah Ayu Pramodhawardhani.
Dalam Candi Borobudur terdapat relief yang menunjukkan masa pada Wangsa
Syailendra, dan hal ini menjelaskan bahwa Candi ini dibangun pada masa kejayaan
Wangsa Syailendra.
Gambar 3.1 Relief Candi Bodobudur yang menunjukkan wangsa Syailendra
- 23 -
Bas-relief di Borobudur menampilkan Raja dan Ratu dengan segenap abdi
pengiringnya. Adegan keluarga kerajaan seperti ini kemungkinan besar dibuat
berdasarkan istana wangsa Syailendra sendiri.
Kerajaan Mataram kuno dibawah pemerintah Sri Maharaja Samaratungga maju
pesat, namun disisi lain raja-raja Mataram kuno pada saat pemerintah Samaratungga
seringkali terjadi perang saudara hingga pertumpahan darah antar raja-raja Mataram
kuno disetiap pergantian kekuasaan, dan saat Samaratungga berkuasa Mataram kuno
dikuasai 2 wangsa yakni wangsa Sanjaya berkuasa di timur jawa tengah serta wangsa
Syailendra berkuasa diselatan (Madhori, 1997), wilayah jawa tengah yang berujung
pembunuhan dan tak kalah ironisnya hancurnya istana beserta ibukota kerajaan dampak
dari perang saudara antar raja-raja Mataram kuno yang berkepanjangan.
Latar belakang inilah yang mendorong raja Samaratungga berupaya menyatukan
kembali Wangsa Syailendra, wangsa yang muncul abad ke-8, dan Wangsa Sanjaya
adalah penguasa awal atau pendiri kerajaan Mataram kuno dengan cara mengadakan
perkawinan politik dengan menikahkan putrinya nan cantik Pramodyawardhani
(Wangsa Sailendra) dengan Rakai Pikatan (Wangsa Sanjaya) (Madhori, 1997).
Pemerintahan Samaratungga berbeda dengan pola pemerintahan sebelumnya, dimana
Samaratungga lebih mengedepankan pengembangan agama dan budaya. Pengembangan
agama maupun budaya yang dimasa pemerintahan Samaratugga yakni menyelesaikan
pembangunan Candi Borobudur dengan arsitek yang cerdas, yang sebelumnya sudah
mulai dibangun oleh raja Mataram kuno sebelumnya. Pembangunan candi Borobudur
yang terus diselesaikan dimasa pemerintahan Samaratungga memiliki sisi menarik,
dimana pembangunan candi Borobudur melibatkan masyarakat Mataram kuno yang
- 24 -
dalam praktik keagamaan terdiri agama hindu dan budha yang tetap memegang
toleransi tinggi serta hidup rukun bergotong royong dalam membangun candi
Borobudur. Dan hal ini terjadi pasca perkawinan Pramodawardhani dengan rakai
Pikatan yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat Mataram kuno ketika itu
(Madhori, 1997).
Sedangkan pada masa tersebut, Candi Borobudur lebih berfungsi sebagai
(Sutanto, 1998):
Sebagai tempat penyimpanan relief (peninggalan – peninggalan yang dianggap suci:
benda – benda, pakaian, tulang – belulang sang Budha arhat dan biksu terkemuka),
dimakamkan juga dhatuganbha (dagoba)
Sebagai tanda peringatan dan penghormatan sang Budha
Sebagai lambang suci umat Budha
Kira-kira kurang lebih selama 150 tahun Candi Borobudur digunakan sebagai
pusat ziarah waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan usianya dihitung dari saat
para pekerja membangun bukit Borobudur dengan batu-batu dibawah pemerintah
Samaratungga, sekitar tahun 800-an. Demikian berakhirnya kerajaan Mataram tahun
930, pusat kehidupan dan kebudayaan Jawa bergeser ke Timur (Sutanto, 1998).
3.2.2 Agama Budha Pada Zaman Kerajaan Sailendra
Informasi mengenai keadaan Agama Buddha pada masa Kerajaan Sailendra
nampaknya lebih jelas dibanding pada masa Kerajaan Sriwijaya. Hal ini dikarenakan
sumber-sumber yang memberi informasi mengenai Agama Buddha lebih banyak,
misalnya dengan keberadaan prasasi-prasasti dan bangunan-bangunan seperti candi.
- 25 -
Sekitar tahun 775 sampai dengan 850 di daerah Bagelan dan Yogyakarta, di Jawa
Tengah berkuasalah raja-raja dari wangsa Sailendra yang memeluk Agama Buddha dan
wangsa Sanjaya yang memeluk agama Hindu-Shiva. Inilah jaman keemasan bagi
Mataram dan negara pada saat itu aman dan makmur karena kedua wangsa (dinasti) itu
saling menolong satu sama yang lain dalam mendirikan tempat-tempat suci (candi). (
Bhagavant, 2013)
Di kerajaan SYailendra agama yang dipeluk adalah Agama Buddha Mahayana.
Hal ini dapat diketahui dari peninggalan-peninggalan sejarah dan candi dari kerajaan ini
yang bercorak Mahayana. Walaupun kerajaan Sailendra banyak mendirikan candi
namun masih terbilang sedikit bila dibandingkan dengan candi yang dibangun oleh
kerajaan Sanjaya. Selain berdasarkan prasasti-prasasti yang ada, bahwa Agama Buddha
yang berkembang adalah Buddha Mahayana, jelas terlihat dari candi di desa Kalasan -
yang kemudian diabadikan sebagai nama candi tersebut.
Candi ini dipergunakan untuk pemujaan kepada Tara, pemujaan kepada
Bodhisattva Avalokitesvara, peresmian rupang (arca) Bodhisattva Manjusri, dan
sebaginya. Nampaknya, pada masa ini kerajaan di Jawa Tengah masih ada hubungan
yang erat dengan India, sebab ada juga berita bahwa seorang guru dari Gaudadwipa
(Bengala) yang memimpin upacara pada waktu peresmian rupang Manjusri. Demikian
juga diberitakan diprasasti lain bahwa ada orang dari Gujarat yang senantiasa
melakukan kebaktian di candi tertentu. Dugaan itu berasal dari berita di India. Raja
Dewapala dari dinasti Pala (Bengala) pada tahun pemerintahannya yang ke-39 (antara
tahun 856 sampai 860) menghadiahkan beberapa desa untuk keperluan pemeliharan
- 26 -
sebuah vihara di Nalanda, yang didirikan oleh Balaputra, raja dari Suwarnadwipa
(Sumatera), cucu raja di Jawa (Bhagavant, 2013).
Keadaan di Jawa Tengah tidaklah sama dengan keadaan di Sriwijaya yang
menjadi pusat Agama Buddha. Namun, aliran Mahayana yang bagaimanakah yang
berkembang di Jawa Tengah? Pertanyaan ini sukar untuk dijawab. Tapi, yang perlu
diperhatikan adalah apa yang tertera pada prasasti Kalurak (782) yang agaknya
berhubungan dengan peresmian rupang Manjusri. Disebutkan dalam prasasti itu bahwa
Manjusri selain disamakan dan anggap sebagai salah satu perwujudan dari Triratna
(Buddha, Dhamma, dan Sangha), Ia juga disamakan dan anggap sebagai salah satu
perwujudan dari Trimurti yaitu Brahma, Vishnu dan Mahesvara (Shiva). Hal ini
menimbulkan suatu teori bahwa telah terjadi sinkretisasi (penyerasian, pencampuran)
antara Agama Buddha Mahayana dengan agama Hindu di Jawa Tengah. Bagi para
pengikut Mahayana di Jawa Tengah, agaknya para Bodhisattva tidak dibedakan dengan
dewa dari agama Hindu (Bhagavant, 2013).
Terdapat candi-candi yang menjadi bukti keberadaan Agama Buddha di Jawa
Tengah. Pada masa itu, ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang Agama
Buddha, sangatlah maju. Kesenian - terutama seni pahat, mencapai taraf yang sangat
tinggi. Seniman-seniman nusantara telah menghasilkan karya seni yang mengagumkan,
misalnya candi Borobudur, Pawon, Mendut, Kalasan, dan Sewu. Dari candi-candi
tersebut memberikan kita penjelasan yang lebih banyak. Selain candi-candi tersebut di
atas, sebenarnya masih banyak lagi candi-candi yang didirikan atas perintah raja-raja
Sailendra. Tetapi yang paling besar dan paling indah serta terkenal adalah Candi
Borobudur yang dibangun pada masa Raja Samarottungga (Bhagavant.com, 2013).
- 27 -
Dalam memahami filosofi dibalik kemegahan Borobudur, kita harus
memandang bangunan tersebut sebagai suatu satu kesatuan. Borobudur yang
mengandung filosofi Mahayana dan juga Tantrayana (Vajrayana) ini, secara
menyeluruh mengungkapkan gambaran mengenai alam semesta atau kosmos.
Borobudur terbagi atas tiga bagian, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu dan Arupadhatu.
Kamadhatu adalah tingkat hawa napsu dan ini digambarkan dengan jelas pada bagian
bawah atau kaki candi. Di sini merupakan kehidupan yang terikat oleh hawa napsu dan
segala hal yang berbau duniawi. Rupadhatu adalah tingkat dunia rupa, atau alam yang
terbentuk, yang digambarkan pada lima teras yang menggambarkan kehidupan Buddha
Gotama. Arupadhatu adalah tingkat alam yang tak berupa, tidak berbentuk. Pada tingkat
teratas terdapat sebuah stupa yang kosong, yang menggambarkan sunyata atau Nirvana.
Borobudur adalah tempat untuk bermeditasi, tempat untuk merenung (Bhagavant,
2013).
Mengingat bahwa Borobudur dibangun diatas bukit, agaknya pembangunan
Borobudur itu dijiwai oleh gagasan Indonesia kuno, yaitu tentang adanya tempat suci
yang berbentuk teras, yang biasanya dipakai untuk menghormati nenek moyang, dan
terletak diatas bukit. Oleh karena itu maka kiranya pemujaan kepada Bodhisattva sudah
dipandang sebagai alat untuk menghormati nenek moyang mereka yang sudah
meninggal. Jika demikian maka Agama Buddha pada waktu ini sudah dipengaruhi oleh
cita-cita keagamaan Indonesia asli (Bhagavant, 2013).
- 28 -
3.2.3 Sosio Culture masa Syalendra
Masuknya Syailendra ke ketanah jawa sebagai sebuah kerajaan, ditandai dengan
mundurnya wangsa Sanjaya ke Pegunungan Dieng, Wonosobo, di wilayah Jawa Tengah
bagian utara. Menyingkirnya wangsa, ternyata menyebabkan perpecahan budaya di
kalangan rakyat, hal ini disebabkan oleh banyak diantara mereka yang masih setia
kepada wangsa, memutuskan untuk mengikutinya wangsa sanjaya ke wonosobo. Dan
sisanya tergerus budaya Buddha bermazhab Tantrayana yang dibawa oleh syailendra.
Pada masa kepemimpinanya raja syailendra banyak melakukan penyebaran
agama Buddha kepada masyarakat yang berada di jawa tengah, khususnya bagian
selatan. Pada masa penyebaran agama Buddha, Raja raja syailendra menarik perhatian
rakyat dengan membangun tempat tempat suci agama Buddha, dengan sangat indah
seperti yang ada di kamboja dan india (Hafizul, 2013). Selain itu raja syailendra juga
berperilaku sederhana dan tidak membeda bedakan kasta seperti kerajaan hindu lainnya,
sehingga kerjaan ini mudah diterima dan dan dicintai rakyatnya.
Selain menyerbakan ajaran agama Buddha, raja syailendra juga mengajarkan
kepada masyarakat cara bercocok tanam, dan melakukan pengairan, dalam melakukan
aksinya raja syailendra tidak segan segan turun langsung untuk berbaur dengan rakyat
jawa, aksi tersebut banyak diceritakan di beberapa prasasti yang mengukir raja
syailendra berada di tengah masyarakat jelata (Gianaro, 2010). inilah juga yang menjadi
salah satu alasan rakyat sangat mencintai kerajaan syailendra, dengan selalu turut serta
dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh kerajaan, yang salah satunya adalah
pembangunan candi Borobudur.
- 29 -
Dari mulai awal pembangunan kerajaan, sampai proses pembangunan candi,
kerajaan syailendra telah berganti kempempinan sebanyak 3 kali, tetapi struktur
pembangunan bangunan candi, hampir tidak ada yang berubah, hal ini menunjukan
bahwa ilmu pembangunan telah dibawa oleh raja pertama syailendra, dan terus
diturunkan kepada raja raja selanjutnya dan jika dilihat dari pola pembangunanya candi
candi yang dibangunan hampir sama dengan yang ada di india dan kamboja (History
end, 2011).
Dari hasil bangunan candi yang ada saat ini, terlihat bagaimana raja syailendra
telah mampu mengorganisir pekerja bangunan untuk menciptakan struktur bangunan
raksaksa yang belum pernah ada sebelumnya, hal ini mencerminkan bagaimana
masyarakat jawa sangat mencintai agama buddha, sehingga mau melakukan gotong
royong untuk membuat bangunan semegah candi Borobudur. Dengan adanya
pembangunan candi, kehidupan masyarakat jawa saat itu jugapun ikut terpusat pada
kegiatan bangunan candi, yang berada di wilayah jawa tengah bagian selatan, yang
sampai sekarang dikenal dengan nama Yogyakarta pusat Jawa tengah.
3.3 Ide-Ide Masa Lalu dan Pemaknaannya di Masa Sekarang
Banyak nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung pada Candi Borobudur, selain
yang ditengarai ada di masa lalu, yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita saat ini.
Nilai-nilai masa lalu dan masa kini sendiri tidak terlepas satu sama lain. Untuk
mengetahui nilai-nilai yang ada saat ini, kita bisa meninjau kembali makna bagian-
bagian maupun keseluruhan dari fisik Candi Borobudur serta nilai-nilai yang
menyertainya sekarang.
- 30 -
Berikut penjelasan nilai-nilai yang berkembang saat ini menurut bagian-bagian
fisik Candi Borobudur:
Tingkatan
Pada tahun 1929 Prof. Dr. W.F. Stutterheim telah mengemukakan teorinya, bahwa
Candi Borobudur itu hakekatnya merupakan ―tiruan‖ dari alam semesta yang menurut
ajaran Buddha terdiri atas 3 bagian besar, yaitu:
Bagian ―kaki‖ melambangkan Kamadhatu, yaitu dunia yang masih dikuasai oleh
kama atau nafsu (keinginan) yang rendah, yaitu dunia manusia biasa seperti dunia.
Rupadhatu, yaitu dunia yang sudah dapat membebaskan diri dari ikatan nafsu,
tetapi masih terikat oleh rupa dan bentuk, yaitu dunianya orang suci dan merupakan
―alam antara‖ yang memisahkan ―alam bawah‖ dengan Arupadhatu, yaitu ―alam atas‖
atau nirwana, tempat para Buddha bersemayam, dimana kebebasan mutlak telah
tercapai, bebas dari keinginan dan bebas dari ikatan bentuk dan rupa. Karena itu bagian
Arupadhatu itu digambarkan polos, tidak berbentuk relief pada Patung-patung Dhayani
Buddha
Nilai-nilai ini masih hidup di tengah-tengah masyarakat, terutama disebabkan oleh
masih banyaknya para penganut agama Buddha yang mempergunakan serta memaknai
dengan hal yang sama ketika melaksanakan proses peribadatan.
Stupa
Pada awalnya, stupa didirikan untuk dijadikan lambang dari Buddha itu sendiri
sehingga dahulu banyak dibangun stupa yang menandakan besarnya pengaruh agama
Buddha itu sendiri. Pendirian stupa tersebut merupakan pembuktian bahwa Buddha
benar-benar ada di wilayah tersebut.
- 31 -
Namun hal yang unik dari Candi Borobudur adalah stupa Candi Borobudur
merupakan bagian dari candi. Sedangkan di wilayah lain, stupa merupakan bangunan
tersendiri yang terpisah dari candi. Hal ini menjadi khas bangunan stupa di Indonesia.
Hal inilah yang kemudian menjadikan stupa di Candi Borobudur sebagai simbol
tertinggi Buddha dan juga sebagai representasi alam semesta. Tergambar melalui tiga
tingkatan, antara lain adalah dimana keinginan manusia dipengaruhi oleh dorongan
negatif, ketika manusia itu memiliki kontrol terhadap dorongan negatif serta berusaha
melenyapkannya dengan dorongan positif, dan ketika manusia tidak lagi dibatasi oleh
keinginan duniawi (Buddhanet, 2012). Selain itu pula, bentuk melingkar dalam stupa di
Candi Borobudur mencerminkan keabadian yang tanpa awal dan tanpa akhir, tenang,
dan murni di dalam dunia yang tak memiliki bentuk pasti (Hayes, 2010).
Penempatan stupa yang disatukan dengan bangunan Candi Borobudur
dimaksudkan untuk menjadi karya arsitektur Buddha sebagai karya yang monumental
sebagai kebangkitan arsitektur pada kala itu. Belum lagi dengan bentuknya yang seperti
teratai, yang merupakan bunga suci Buddha, diharapkan bisa muncul refleksi dari
campuran ide antara konsep nirwana milik Buddha dengan pemujaan leluhur adat di
wilayah tersebut (UNESCO, 2013).
Melalui stupa pula, terdapat pemikiran suci Buddha yang menunjukkan jalan
pencerahan. Menjadikan siapapun yang membangun stupa menjadi murni dari hal-hal
negatif dan halangan dalam mengumpulkan pahala sehingga bisa dilancarkan dalam
mencapai tujuan akhir. Adapun sepuluh manfaat membangun stupa, antara lain:
1. Siapa yang membuat 1000 stupa, maka dia akan dibesarkan dan dianggap bisa
memegang ajaran kebijaksanaan.
- 32 -
2. Akan dilahirkan kembali sebagai raja setelah mengalami kematian tanpa harus
ke alam yang lebih rendah.
3. Akan menjadi matahari yang bersinar untuk dunia dan menjadi sempurna.
4. Akan mampu mengingat kehidupan masa lalu dan melihat kehidupan di masa
depan.
5. Akan dapat secara ekstensif mendengarkan Dharma.
6. Menghilangkan semua karma negatif dan halangan-halangan.
7. Para makhluk hidup akan selalu dilindungi oleh Buddha.
8. Mengubah penderitaan menjadi kelahiran kembali ke arah keberuntungan untuk
memenuhi Dharma.
9. Dapat menyembuhkan orang-orang dengan penyakit serius.
10. Mengakumulasi pahala yang luas dan membawa kesuksesan dan kebahagiaan
untuk kehidupan di masa depan (Stupa.org, 2013).
Kepercayaan-kepercayaan ini tidak hanya dimaknai oleh para penganut agama
Buddha saja, melainkan oleh para penganut agama lain yang biasanya berkunjung ke
Candi Borobudur yang timbul dalam berbagai bentuk mitos.
Relief
Dari apa yang terlihat di dalam bangunan candi tersebut ada makna lain selain
candi yang merupakan tempat peribatan agama budha saja, melainkan pesan yang
terkandung dalam relief-relief yang berhubungan dengan ajaran agama Buddha.Hhal ini
dilihat dari ajaran agama buddha yang terkandung di kitab suci agama budha.Selain itu,
- 33 -
nilai-nilai seni relief ini bisa ditelusuri sebagai pengaruh dari berbagai aliran seni India,
Eropa, maupun Nusantara (Munandar, 2009).
Makna yang utama yang tergambar di candi Borobudur salah satunya adalah :
1. Hukum Karmavibangga
Karmawibhangga adalah relief yang menggambarkan suatu cerita yang
mempunyai korelasi sebab akibat (hukum karma).Di zona Kamadhatu, beberapa
relief-relief Karmawibhangga menggambarkan hawa nafsu manusia, seperti
perampokan, pembunuhan, penyiksaan, dan penistaan. Tidak hanya
menggambarkan perbuatan jahat, relief Karmawibhanga yang dipahat di atas 160
panel juga menggambarkan ajaran sebab akibat perbuatan baik .
Setiap panel bukanlah cerita naratif (berseri) dan berisi kisah-kisah tertentu
yang di antaranya menggambarkan perilaku masyarakat Jawa Kuna masa itu,
antara lain perilaku keagamaan, mata pencaharian, struktur sosial, tata busana,
peralatan hidup, jenis-jenis flora dan fauna, dan sebagainya. Secara keseluruhan
itu menggambarkan siklus hidup manusia, yaitu: lahir - hidup - mati (samsara).
Kamadhatu adalah gambaran dunia yang dihuni oleh kebanyakan orang,
atau dunia yang masih dikuasai oleh kama atau "nafsu rendah". Karenanya zona
ini berada di tingkat paling bawah Borobudur dan kini tertutup oleh pondasi
penyokong bangunan sehingga tidak terlihat (kecuali pada sisi Selatan terbuka
sedikit). Ada dugaan bahwa tertutupnya zona ini dikarenakan untuk memperkuat
struktur atau pondasi bangunan. Akan tetapi, dugaan lain menyebutkan bahwa hal
tersebut adalah untuk menutupi konten-konten cabul dari relief tersebut. Untuk
melihat relief pada zona ini, Anda dapat mengunjungi Museum Karmawibhangga
- 34 -
yang memajang foto-foto di Kamadhatu yang sengaja diambil agar tetap dapat
dinikmati pengunjung.
Kamma adalah kata bahasa Pali dan Karma adalah kata Sanskerta yang
secara singkat berarti perbuatan, yaitu setiap perbuatan didahului oleh suatu sebab
dan kemudian setelah itu dilakukan akan menimbulkan akibat. Relief
Karmawibhangga sejatinya menggambarkan hukum karma yang berada dalam
ajaran Buddha, dimana di dalam kehidupan manusia terdapat yang disebut dengan
hukum sebab-akibat, yang mempengaruhi perjalanan siklus hidup manusia,
kemana dan bagaimana kehidupan tersebut akan berlangsung.
Semua perbuatan menimbulkan akibat dan akibat ini merupakan pula sebab
yang akan menghasilkan akibat lain, dan begitulah seterusnya, sehingga kamma
juga disebut sebagai hukum sebab-akibat. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati
dengan perbuatan kita, supaya akibatnya senantiasa bersifat baik, seperti
menolong makhluk dan membahagiakannya, sehingga perbuatan itu akan
membawa suatu kamma-vipaka (akibat-kamma) yang baik dan memberikan
kepada kita untuk melakukan kamma yang lebih baik lagi. Adapun pembagian
karma :
Menurut waktu:
• Uppajjavedaniya-kamma, adalah karma yang akibatnya dialami dalam
kehidupan setelah hidup sekarang ini.
• Aparaparavedaniya-kamma, adalah karma yang akibatnya akan dialami
dalam kehidupan-kehidupan berikutnya.
• Ahosi-kamma, adalah karma yang tidak member akibat karena jangka
waktunya untuk memberikan akibat telah habis atau karena karma
- 35 -
tersebut telah menghasilkan akibatnya dan secara penuh sehingga
kekuatannya habis sendiri.
Menurut kekuatan:
• Garru kamma, adalah karma yang paling berat diantara semua
karmalainnya karena sifatnya yang amat kuat. Selama karma ini masih
menghasilkan akibatnya, tak ada karma lainnya yang berkesempatan
untuk menghasilkan akibatnya (menjadi masak).
• Bahula-kamma, adalah karma yang sering dan berulang-ulang dilakukan
oleh seseorang melalui saluran badan jasmani, ucapan, dan pikiran,
sehingga tertimbun dalam wataknya.
• Asannamarana-kamma, adalah karma yang diperbuat seseorang pada
saat menjelang kematian, atau dapat pula berupa perbuatan yang dahulu
dilakukan, jadi ingat kembali dengan amat jelas saat diambang
kematiannya.
• Kattata-kamma, adalah suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan
kehendak tertentu, dan perbuatan ini dilakukan hanya sekali saja atau
beberapa kali, namun bukan perbuatan yang dilakukan terus-menerus.
Menurut fungsi:
• Janaka-kamma (karma penghasil), adalah karma yang berfungsi
menghasilkan.karma macam ini dapat dibandingkan dengan seorang
ayah-ibu dalam fungsinya membawa seorang dalam kelahiran baru.
Menurut Budha, apabila janaka-kamma telah menyebabkan suatu
kelahiran, maka tugasnya sebagai karma penghasil berakhir.
- 36 -
• Upattahambhaka-kamma (karma penguat), adalah karma yang berfungsi
membantu memperkuat apa yang telah dihasilkan oleh janaka-kamma
sesuai dengan macam dan sifatnya. Jadi apabila janaka-kamma baik,
kamma penguat ini membantu sehingga keadaanya lebih baik; demikian
pula sebaliknya.
• Uppapilika-kamma (karma-pelemah), adalah karena yang berfungsi
menandingi pengaruh dari apa yang telah dihasilkan oleh janaka-kamma,
memperlemah kekuatannya atau mempersingkat waktunya dalam
menghasilkan akibatnya.
• Upaghataka-kamma (karma penghancur), adalah karma yang mempunyai
kategori sama dengan karma pelemah di atas, karena fungsinya
menentang atau menghancur kekuatan dari janaka-kamma.
Menurut kedudukannya:
• Akusala-Kamma: Perbuatan buruk yang akan masak di alam keindriaan.
Ada sepuluh (10) tindakan jahat yang disebabkan oleh perbuatan badan
jasmani, ucapan dan pikiran yang menghasilkan Kamma jahat. Akar
dari tindakan jahat ini adalah keserakahan (lobha) akan keindriyaan,
kebencian (dosa), dan kebodohan batin (moha). Sepuluh Tindakan jahat
ini antara lain (Munandar, 2009):
1. Membunuh
2. Mencuri
3. Pelanggaran susila
4. Berbohong
5. Memfitnah
- 37 -
6. Kata-kata kasar
7. Pergunjingan
8. Rasa tamak
9. Keinginan jahat
10. Pandangan salah. (Munandar, 2009)
• Kamavacarakusala-Kamma: Kamma baik yang akan masak di alam
keindriaan. Kamavacarakusala-kamma terbagi menjadi tiga (3) macam ,
yaitu:
1) Kusala-Kaya-Kamma (perbuatan baik melalui jasmani).
2) Kusala-Vaci-Kamma (perbuatan baik melalui perkataan).
3) Kusala-Mano-Kamma (perbuatan baik melalui pikiran). (Munandar,
2009)
Hukum karma merupakan hukum yang sangat populer tidak hanya di
kalangan para penganut Buddha saat ini saja, tetapi juga oleh banyak kalangan
masyarakat non-Buddha.Bahkan, istilah ‗karma‘ sebagai saduran dari kamma ini
sering disandingkan dengan ajaran-ajaran agama Islam, Kristen, dan agama-
agama lain di Indonesia tentang hukum sebab-akibat.Misal, Islam menyebutnya
sebagai qishas (hukuman setimpal) maupun perhitungan pahala-dosa dan surga-
neraka di hari setelah kiamat.
2. Lalitawistara (cerita para Budha)
Lalitavistara mengilhami terciptanya karya besar lain oleh Asvaghosa yaitu
Buddha-caritta yang juga merupakan hikayat kehidupan Buddha Gautama
Shakyamuni, dalam bentuk seloka yang terdiri atas dua puluh delapan kumpulan
syair panjang yang amat indah dan lebih mendetail dari sumbernya yang asli
- 38 -
yakni Lalitavistara. Mengingat Asvaghosa seorang sastrawan besar, banyak yang
mengakui ceritera tentang Buddha di dalam Buddha-Carrita sesungguhnya lebih
hidup dan lebih menawan. Lalu mengapa Borobudur memilih Lalitavistara dan
bukan Buddha-Caritta sebagai relief lanjutan dari Jataka dan Avadhana? Sehingga
pernah suatu saat kami ditanyai oleh seorang guru besar asing, guest lecture dari
sebuah grup tour Borobudur–enthusiast, bahwa mengapa pada Borobudur yang
agung ini tidak tampak bagian akhir dari kehidupan Sang Buddha yakni
Mahaparinirva yang termasyur itu? Disini kita harus mencoba mencari tahu
mengapa yang menjadi pilihan adalah Lalitavistara dan bukan Buddha-Caritta.
(HPI Jogja, 2010)
Disini kita menemukan bahwa sutra-sutra yang akan dimuat dipilih dengan
pertimbangan yang hati hati, agar dari sutra yang berdiri sendiri, sanggup terjalin
dalam satu rangkaian dengan sutra berikutnya dalam relief, berdasarkan nilai nilai
filosofis ajaran Buddha dari berbagai aliran. Hal ini dimungkinkan karena seperti
yang telah disinggung terdahulu, bahwa kebanyakan Sutra ditulis kedalam bahasa
Sansekerta, sementara Sansekerta memungkinan penafsiran ganda yang , maka
ada kebebasan interpretasi yang terkondisikan oleh kebutuhan merangkaikan kan
beberapa sutra menjadi satu bagian yang utuh untuk tujuan visi dan misi
borobudur.
Contoh yang sangat jelas tampak pada bagian awal panil relief yang
menggambarkan surga Tusita dengan Bodhisattva, disini dapat diibaratkan
perjuangan Buddha lewat ratusan kali kelahiran kembali akhirnya telah mencapai
tingkat yang amat mulia di surga Tusita. Namun belum mencapai puncak
- 39 -
kebebasan sehingga harus dilahirkan kembali sebagai seorang Pangeran di
Kapilavastu (HPI Jogja, 2010).
3. Jataka / Avadana
Kondisi Relief Candi Borobudur memprihatinkan karena sebagian relief
tidak dapat dibaca dengan sempurna, sebagian relief hilang, keropos atau susunan
batu berelief tertutup batu polos karena batu aslinya tidak ditemukan.Kondisi ini
menyulitkan peneliti untuk dapat membaca, kemudian mengidentifikasi cerita
pada relief tersebut. Pada tingkat I Candi Borobudur bagian dinding b dan bagian
langkan, serta tingkat II bagian langkan terdapat pahatan relief cerita
Jātaka/avadana yaitu perjalanan Bodhisattva untuk menyempurnakan sifat-sifat
luhur (Pāramita). Relief pada dinding b tingkat I berjumlah 120 pigura, pada
langkan a berjumlah 372 pigura, langkan b berjumlah 128 pigura, jumlah relief
pada langkan tingkat I adalah 500 pigura. Relief Jātaka/avadana pada tingkat II
pada bagian langkan berjumlah 100 relief, sehingga relief Jātaka/avadana pada
Candi Borobudur secara keseluruhan berjumlah 720 pigura/panel.
Cerita-cerita Jātaka/avadana bersumber pada Kitab Jātakamala atau
untaian (cerita) Jātaka karya penyair Aryasura yang hidup pada abad IV Masehi
dan lainnya kemungkinan bersumber pada Kitab Jātaka, serta Avadana yang
ceritanya dihimpun dalam Kitab Divyavadāna yaitu perbuatan-perbuatan mulia
kedewaan dan Kitab Avadanasalaka atau seratus kitab Avadana. Perbedaan antara
Jātaka dan avadana adalah bahwa dalam avadana pelaku utamanya bukan
Bodhisattva sendiri melainkan orang lain, tetapi secara esensial Jātaka merupakan
tak lain dari avadana dengan Buddha, calon Buddha Sakyamuni yang ditampilkan
dalam cerita sebagai tokoh utama. Jātaka dan avadana diperlakukan dalam satu
- 40 -
seri dan sama tanpa perbedaan jelas, tidak ada sistem tertentu dan jelas dalam
pergantian relief. Pada baris bawah relief dinding galeri pertama sebagian besar
menggamabrkan avadana, sedangkan beberapa Jātaka sebagai variasi.Sistem pada
baris atasnya pada langkan sangat berbeda yaitu semua relief merupakan Jātaka
dan hanya ada beberapa avadana (Soekmono, 1976: 26).
Jumlah tertentu dari cerita-cerita Avadana digambarkan secara rinci dalam
ukuran besar secara berurutan pada seri Ib, sedangkan beberapa lainnya terdapat
di pagar galeri pertama (Kempers, 1967: 107). Pada bagian dalam pagar langkan
tingkat 1 terdapat dua tingkat relief yang menggambarkan kehidupan Buddha,
pada bagian atas bersumber pada Jātakamala yang dikumpulkan pada abad
keempat, tetapi di sudut timur laut panel tingkat atas menggambarkan lain teks,
Awadana (Dumarcy, 1978: 33). Panel pertama berjumlah 135 di barisan atas
galeri pertama, khusus berisi 34 cerita Jātakamala. Sisa 237 panel
menggambarkan cerita dari sumber lain, seperti halnya seri bawah pada pagar
langkan galeri kedua (Soekmono, 1976: 29). Panel relief berjumlah 135tersebut
telah teridentifikasi sebagai penggambaran 34 buah cerita saduran dari Jātakamala
atau untaian (cerita) Jātaka karya penyair Aryasura, selebihnya yang berjumlah
237 buah menggambarkan cerita-cerita dari sumber lain. Sisa relief
Jātaka/Avadana berjumlah 348 juga berasal dari sumber lain atau mungkin Kitab
Jātaka. Deretan relief yang di bawah dan deretan relief pada langkan lorong
tingkat ke dua tidak semuanya Jātaka (Soekmono, 1976: 28-29; Joesoef, 2004:
118; Kempers, 1976: 107). Kesesuaian 34 cerita saduran Jātakamala atau untaian
(cerita) Jātaka karya penyair Aryasura dengan relief Candi Borobudur Jātaka telah
diidentifikasi masing-masing ceritanya dari cerita ke-1 sampai cerita ke-23 oleh
- 41 -
John Miksic, Marcello Tranchini, dan Anita Tranchini dalam buku ―Borobudur:
Golden Tales of the Buddhas‖ (Borobudur.tv, 2013).
4. Gandavyuha Sutra
Relief yang terdapat pada dinding canding sebenarnya merupakan refleksi
dari kitab suci Agama Buddha . Dalam kitab suci Mahayana terdapat Sembilan
Dharma yaitu (1) Astasahasrika-Prajnaparamita, (2) Gandavyuha, (3)
Dasabhumisvara, (4) Samadhi-raga, (5) Lankavatara, (6) Saddharma-Pundarika,
(7) Tathagata-guhyaka, (8) Lalitavistara, (9) Suvarna-Prabhasa . Kesembilan teks
daharma teresebut kemudian digunakan untuk menghiasi setiap dinding bangunan
candi. Dan pada bagian teratas candi , merupakan refleksi dari sutra Gandavyuha.
Sutra gandavyuha sendiri, merupakan teks sutra yang paling banyak dijadikan
inspirasi dalam bangunan candi, hal ini disebabkan dengan makna dari
gandavyuha sendiri yang berarti ―memasuki dharmadhutu‖ , yang diharapkan
kepada siapa saja yang memasuki candi ini, sama dengan mamasuki kehidupan
darma.
Teks Gandavyuha pernah ditemukan di nepal, dan sampai saat ini teks
gandavyuha masih tersimpan rapih di kuil Maitreya di nepal .Dari bentuknya sutra
gandavyuha disusun dalam bentuk narasi yang sangat imaginatif dan penuh
dengan simbol simbol.Secara keseluruhan teks gandavyuha menceritakan
perjalanan seorang anak saudagar kaya raya yang bernama Sudhana. Sudhana
mendapat nasehat sang bodhisatva manjustri untuk mencari kalyana (guru) yang
akan membimbing kehidupan kebodhisatvaannya hingga akhirnya dapat
menemukan bodhisatva maitreya di pagoda nanti. Dari nasihan bodhisatva
tersebutlah, Sudhana akhirnya mengembara ke sana ke sini untuk berguru guna
- 42 -
mendapatkan pengetahuan tertinggi mengenai arti kehidupan. Cerita perjalanan
Sudhana dalam menemukan arti kehidupan semakin menarik, yang mana dalam
teks ini juga menceritakan berbagai alat transportasi yang digunakam Sadhana
seperti kereta kuda dan gajah, kemudian kehidupan di setiap kota kata yang ia
singgahi. hingga sampai pada adegan terakhir di puncak gunung semeru, dimana
ia berlutut di hadapan para gurunya, dan kisah ini beraakir di istana maitreya
seperti yang telah di ramahalkan oleh bodhisatva Manjustri dahulu .
Dalam bangunan candi, Rangkaian terakhir relief yang terdapat di teras
bagian atas diambil dari lanjutan teks ini, yang disebut Bhadracari, dimana
Sudhana bersumpah untuk menjadi Bodhisattva, dan mengikuti contoh
Bodhisattva tertentu bernama Samantabhadra Bhadracari; ―Dan kemudian
selanjutnya, Raja Buddha akan datang, yang akan menerima pencerahan di masa
depan, seperti Raja Maitreya yang mulia dan seterusnya, dan akhirnya
Samantabhadra, Sang Buddha Masa Depan‖. Penempatan rangkaian relief pada
tingkat paling tinggi dari candi menunjukkan bahwa ini merupakan teks yang
paling dihormati oleh pendiri Borobudur.Adegan-adegan relief kelihatannya
didesain untuk mendorong para pejiarah agar mengikuti contoh Sudhana ketika
memanjat gunung, yang melambangkan tujuan dan sumber kebijaksanaan
tertinggi.
Setelah mendapati nilai-nilai yang masih berkembang saat ini dari bagian-bagian
Candi Borobudur, kita bisa mendapati nilai-nilai dari Candi Borobudur secara
keseluruhan. Fakta Candi Borobudur sebagai obyek pariwisata saat ini tidak dapat
dipungkiri lagi telah memberikan muatan nilai-nilai kekinian yang baru. Berikut nilai-
- 43 -
nilai kekinian yang masih hidup atau bahkan baru muncul dari keseluruhan Candi
Borobudur:
Politik/Kekuasaan
Praktik-praktik kekuasaan politik maupun, secara khusus, ekonomi-politik banyak
terinspirasi secara langsung maupun tidak langsung oleh Candi Borobudur. Pada tahun
1960an, Presiden RI pertama Soekarno membangun beberapa monumen mahabesar
dalam rangka politik mercusuar seperti Monas (Monumen Nasional) dan Gedung
Canefo (Conference ofthe New Emerging Force) (jakarta.go.id, 2013).Inspirasi
kebesaran Dinasti Syailendra yang direpresentasikan lewat Candi Borobudur nampak
nyata juga direka ulang oleh Soekarno lewat karya-karya besar tersebut. Hanya saja
Syaielandra menonjolkan ilai-nilai Buddha, sedangkan Soekarno menonjolkan nilai-
nilai kemerdekaan, persatuan, dan anti-penjajahan atau imperialisme Barat yang saat itu
menyelimuti kondisi politik Indonesia maupun dunia.
Menurut Purnawan Andra, efek utama dari objektifikasi-wisata Candi Borobudur
adalah reduksi nilai-nilai keagungan budaya kuno masyarakat setempat serta
subordinasi ajaran Buddhauntuk kepentingan komersial serta mempertahankan
hegemoni kekuasaan yang ada (Kompas, 2010). Kepentingan komersial jelas hanya
berorientasi pada keuntungan ekonomis sehingga mengorbankan keaslian dari kearifan
lokal dan kesungguhan dalam penghormatan nilai-nilai setempat.Kemudian, aktivitas-
aktivitas ke-budnha-an tidak luput dari isu komersialisasi, namun lebih jauh lagi, juga
telah memosisikan Buddha sebagai unsur budaya nasional yang bukan utama.Hal ini
terkait dengan hegemoni kekuasaan atau pemerintahan Indonesia saat ini yang
didominasi oleh pemikiran-pemikiran Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas.
- 44 -
Inspirasi
Menurut Daud Aris Tanudirjo, Candi Borobudur memiliki nilai-nilai tak terikat
yang bisa menginspirasi (Tanudirjo, 2013). Kebebasan dalam menginterpretasikan
sangat dianjurkan dan bahkan memang sudah sangat banyak terjadi. Daud memaparkan
bahwa inspirasi-inspirasi dari Candi Borobudur berkenaan dengan Candi Borobudur
sebagai monumen sejarah penting tentang kejayaan masyarakat masa lalu, sebagai
ilham bagi para seniman maupun ilmuan, sebagai buku evolusi manusia, dan sebagai
penginspirasi masyarakat saat ini dengan penekanan aspek pendidikan.
Hubungan Internasional
Candi Borobudur merupakan representasi interaksi antarbangsa yang telah terjadi
bertahun-tahun disertai pertukaran-pertukaran ide di antara para pelakunya, tidak hanya
antara bangsa India dengan masyarakat nusantara, tetapi hingga Eropa (Munandar,
2009). Melalui Candi Borobudur, masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi akan
toleransi dan interaksi antarbudaya yang ternyata mampu mewujudkan suatu
mahakarya. Mahakarya ini dianggap sebuah kemajuan peradaban manusia secara
universal.
Melalui salah satu badan PBB yaitu UNESCO, Candi Borobudur menjadi eksis
dan menjadi peninggalan masa lalu dunia yang tetap hidup di masa kini.Pengakuan
badan PBB ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Candi Borobudur
diakui keberadaannya dan menjadi bukti sejarah kemajuan peradaban manusia pada
masa lalu.Pemikiran-pemikiran Barat yang tertuang dalam organisasi internasional yang
nilai-nilainya diakui secara universal dapat dilihat dari pengakuan UNESCO terhadap
Candi Borobudur pada tahun 1991 sebagai situs warisan budaya dunia. Meski begitu,
- 45 -
keperluan akan pengakuan badan internasional bagi Candi Borobudur memunculkan
pertanyaan baru tentang dominasi-dominasi yang ada pada tatanan dunia saat ini dan
bagaimana posisi Indonesia saat ini.
Secara keseluruhan, nilai-nilai yang ada dan muncul saat ini yang berkaitan
dengan Candi Borobudur bisa dilihat pada tabel berikut:
Bagian-bagian Keseluruhan
Tingkatan Ajaran
Buddha tentang
Kamadhatu,
Rupadhatu, dan
Arupadhatu.
Politik/Kekuasan ―Politik
Mercusuar‖ Soekarno,
Komersialisasi,
Hegemoni
Stupa
Ajaran Buddha
tentang kesemestaan,
kesucian, dan
keabadian serta mitos-
mitos yang
berkembang di
seputarnya.
Inspirasi Bebas
Sejarah, ilham seni
dan ilmiah, buku
evolusi manusia,
inspirasi kekinian
(pendidikan).
Relief Ajaran Buddha
tentang
Karmavibangga,
Lalitawistara, Jataka
Hubungan Internasional Universalisme,
Antarbudaya
- 46 -
/ Avadana, dan
Gandavyuha Sutra
serta akulturasi aliran
seni India, Eropa, dan
Nusantara.
Tabel 3.2 Nilai-nilai Pada Candi Borobudur
3.4 Genealogi Arkeologi Candi Borobudur
ARKEOLOGI
BOROBUDUR
Cara mendokumentasikan
- Mpu Prapanca
- Sir Thomas Stamford
Raffles
- C. Leemans dan JFG
Brumund
- JW Ijzerman
- TH. van Erp dan
Nicholas J. Krom
- W.O.J. Nieuwenkamp
Ide-ide masa lalu
- Kerajaan
- Agama
- Sosio-kultur
masyarakat dalam
masa kerajaan
mataram
(syailendra)
Keterkaitan ide-
ide masa lalu-
sekarang
- Buddha
- Mitos
- Sosio
kultur
masyaraka
t masa kini
ARKEOLOGI-GENEALOGI FOUCAULT
TERHADAP ARSITEK CANDI BOROBUDUR
- 47 -
Arkeologi akan melihat sebuah pola pengetahuan yang dimunculkan dari
peradaban yang eksis saat arsitek tersebut dibuat dan kemudian didokumentasikan
menjadi episteme-episteme yang diskontinuitas atau terpisah dan tidak memiliki
keterkaitan. Terdapat periode sejarah masing-masing saat arsitek tersebut
didokumentasikan dan menjelaskan masa sekarang.
Borobudur merupakan artefak peninggalan kerajaan mataram kuno, peradaban
syailendra, yang kemudian didokumentasikan oleh beberapa pengarang seperti Mpu
Prapanca, Sir Thomas Stamford Raffles, C. Leemans dan JFG Brumund, JW Ijzerman,
Arkeologi
- Objek
- Diskursus (positivitas, apriori
historis, arsip)
- Pola pengetahuan lama – baru
- Periode sejarah –
diskontinuitas
- -Penyebaran wacana – rezim
kebenaran
Genealogi
- Penyelidikan sejarah
- - kekhasan
- Mendiagnosis masa kini
- -konsep power-knowledge
DOKUMENTASI, IDE MASA LALU, IDE
MASA SEKARANG
- BUDDHA
- REZIM KEBENARAN – MITOS, SOSIO
KULTUR
- KEUNIKAN/KEKHASAN (TIDAK HANYA 1
AUTHOR)
- KONSEPSI POWER-KNOWLEDGE
- 48 -
TH. van Erp dan Nicholas J. Krom, W.O.J. Nieuwenkamp. Ketujuh pengarang ini
memberikan deskripsi mengenai Borobudur dari sudut pandang yang berbeda tetapi
terdapat satu kesatuan yaitu didasari oleh agama Buddha dimana arsitek borobudur
menggambarkan arsitek budaya Indonesia, landasan filsafah dan agama, dan sebagai
tempat ibadah agama buddha. Sebagai artefak peninggalan kerajaan mataram kuno,
borobudur merupakan dokumentasi peradaban yang berlangsung saat itu dimana
syailendra mendokumentasikan kehidupan umat buddha saat itu serta nilai-nilai
keagamaan yang dipahat di tiga tingkatan candi borobudur. Dokumentasi pertama
berupa benda yaitu candi, dan kemudian didokumentasikan lagi oleh pengarang
berikutnya dalam buku-buku atau teks-teks yang memuat serangkaian pemaknaan akan
candi borobudur ini. Arsip-arsip tersebut tertuang dalam The History of Java, foto
pertama ―Daguerreotype, monograf, penemuan relief Karmawibhanga, “Annotated
Bibliography of Borobudur”, serta teori teratai di atas danau purba.
Ide pembuatan borobudur pada masa kerajaan mataram kuno, peradaban
syailendra ini mengandung tiga unsur utama, yaitu kerajaan mataram itu sendiri, agama
buddha yang ingin diangkat dan diabadikan oleh syailendra, serta sosio-kultur
masyarakat dalam peradaban tersebut. Pada tahun pembangunan borobudur, bertepatan
dengan kemajuan wangsa syailendra di jawa tengah yang dipengaruhi oleh
kemaharajaan sriwijaya. Pembagunan borobudur ini memakan waktu yang diperkirakan
yaitu 75-100 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peradaban saat itu sangatlah maju dan
merupakan masa-masa kejayaan. Dalam pahatan di relief-relief candi borobudur juga
terdapat penggambaran bagaimana syailendra hidup dan memerintah serta hingga akhir
keruntuhannya yaitu akibat perang saudara yang terjadi di kerajaan mataram kuno.
Sedangkan dari sisi agama, borobudur saat itu merupakan penyimpanan relief
- 49 -
(peninggalan – peninggalan yang dianggap suci: benda – benda, pakaian, tulang –
belulang sang Budha arhat dan biksu terkemuka), dimakamkan juga dhatuganbha
(dagoba), tanda peringatan dan penghormatan sang Budha, dan sebagai lambang suci
umat Budha. Konteks sosio-kultur masyarakat terdokumentasikan dalam tiga tingkatan
candi borobudur yaitu Kamadhatu, Rupadhatu dan Arupadhatu. Dimana masyarakat
percaya akan adanya kehidupan duniawi yang penuh dengan dosa, terikat dengan hawa
nafsu duniawi, lalu pada tingkat kedua yaitu tingkatan diantara alam dunia dan nirvana,
sedangkan tingkatan terakhir mendokumentasikan nirvana atau surga yang menjadi
tempat para dewa, meditasi, dan tempat perenungan.
Borobudur sebagai artefak dalam arkeologi hingga saat ini masih tetap eksis di
Jawa tengah, indonesia, bahkan dalam dunia internasional. Ide-ide pendokumentasian
borobudur oleh wangsa syailendra ini menyebar dan menjadi wacana atas penyebaran
kekuatan agama buddha sebagai peradaban yang hebat saat itu dan juga melambangkan
tiga tingkatan dalam agama budha itu sendiri. Pada masa sekarang, nilai-nilai buddha
masih dimaknai oleh penganut agama buddha dan borobudur memperkuat nilai-nilai
tersebut. Bahkan memberikan sebuah konstruksi bagi masyarakat akan agama buddha
itu sendiri yang dipandang dari mereka yang memang bragama buddha dan mereka
yang beragama lain, memunculkan mitos-mitos yang dipercayai oleh masyarakat yang
ada di jawa tengah, indonesia, dan dunia internasional, serta membentuk sosio-kultural
masyarakat tersebut yang berkaitan dengan candi Borobudur.
- 50 -
BAB IV
KESIMPULAN
Arkeologi melihat bahwa objek merupakan hal penting yaitu artefak dalam hal
ini adalah borobudur , pengkajian arkeologi diperdalam dengan melihat diskursus atau
wacana yang dibicarakan atau dituliskan tersebut melalui positivitas, apriori historis dan
arsip-arsip. Agama buddha merupakan positivitas dimana ada sebuah keterkaitan baik
kesamaan dan perbedaan bagaimana para pengarang mendokumentasikan borobudur
tersebut melalui arsip yaitu candi dan buku-buku teks.
Candi borobudur juga mempunyai keterkaitan dari pola pengetahuan yang lama
dengan pola pengetahuan yang baru yaitu sebagai peradaban zaman wangsa syailendra
yang hanya sekedar tempat ibadah dan kemudian menjadi tempat suci dunia bagi
seluruh umat buddha di dunia. Hal ini melihatkan ada sebuah perluasan dan
perkembangan yang signifikan atas eksistensi candi borobudur ini. Arkeologi juga
menjelaskan bahwa periode sejarah itu diskontinuitas atau terputus-putus sehingga
adalah wajar jika terdapat perbedaan pemahaman atau dokumentasi borobudur tersebut
oleh para pencipta atau pengarangnya. Hal ini terlihat melalui perbedaan pemaknaan
dan pendokumentasian borobudur misalnya dianggap sebagai tempat ibadah dan bahkan
sebagai teratai di atas danau purba.
Lebih lanjut, arkeologi melihat bahwa terdapat sebuah penyebaran wacana untuk
menciptakan rezim kebenaran melalui pendokumentasian artefak tersebut. Borobudur
sendiri secara jelas terlihat menyebarkan wacana atau teks-teks mengenai Buddha
- 51 -
sebagai agama yang hebat pada zama tersebut, dan kemudian memunculkan lagi
kepercayaan masyarakat atas tiga tingkatan kehidupan manusia sehingga rezim
kebenaran yang muncul adalah apa yang dianggap baik dan salah, juga apa yang
dianggap penting dan tidak penting. Bahkan terdapat mitos-mitos yang dimunculkan
serta dibenarkan oleh masyarakat mengenai borobudur tersebut.
Geneaologi menjelaskan bahwa perlu ada penyelidikan sejarah , melihat
kekhasan yang ada, mendiagnosis masa kini dan mempertunjukkan bahwa akhirnya
semuanya adalah sebuah power- knowledge. Genealogi berkaitan dengan arkeologi dan
yang terkait dalam konteks candi borobudur ini adalah penyelidikan sejarah ide-ide
pembuatan candi borobudur serta narasi-narasi kehidupan peradaban tersebut dalam
relief-relief candi. Kekhasan dalam candi borobudur adalah bagaimana pencipta atau
pengarang memiliki interpretasi yang berbeda-beda dalam memaknai hasil dokumentasi
mereka. Diagnosis masa kini berkaitan dengan pola perilaku masyarakat yang ada pada
perdaban terbentuknya borobudur dan masyakarat zaman kini. Dan pada akhirnya
menunjukkan bahwa ada sebuah kekuasaan yang berada di balik wacana yang
dimunculkan.
Borobudur dimunculkan atas sebuah kekuasaan yaitu Wangsa Syailendra yang
ingin menyebarkan agama buddha ke generasi berikutnya walaupun hanya melalui
sebuah candi. Begitu pula dengan pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki oleh
masyarakat buddha dan non-buddha mengenai borobudur, dimana ketika mengingat
borobudur, akan mengingat buddha, dan beberapa konsep atau mitos lainnya yang
mengglobal dan dianggap ada bahkan dipercayai lebih lanjut lagi dilakukan.
- 52 -
DAFTAR PUSTAKA
Aldicke (2012) Kerajaan syailendra [WWW] Available from:
http://rapendik.com/program/halo-pendidikan/budaya-sejarah/182-kerajaan-
sailendra [Accessed 21/10/2013]
Archipeddy. Candi Budha Borobudur.[WWW] Available From:
http://archipeddy.com/histo/nusantara/borobudur.html [Accessed 08/10/2013]
Asia Society Museum (2013) Sculpture of a Seated Buddha [WWW] Available from:
http://www.asiasocietymuseum.org/himalayan/seatedBuddha.htm [Accessed
03/10/2013]
Bhagavant.com (2013) Sejarah Buddhisme Indonesia [WWW] Available from:
http://bhagavant.com/home.php?link=sejarah&tipe=sejarah_buddhisme_Indones
ia_2 [Accessed 21/10/2013]
Balai Konservasi Borobudur (2011) Candi Borobudur Available from:
http://konservasiborobudur.org/v3/candi-borobudur.html [Accessed
10/10/2013].
BBC (2013). A History of the World: Borobudur Buddha Head. [WWW] Available
from:
http://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/objects/CPbWMMoFSnmUlSHF3dk
5A [Accessed 15/10/2013]
Blog.sribu.com (2012) makna di balik kemegahan candi Borobudur. [WWW]
Available from http://blog.sribu.com/2012/05/04/makna-di-balik-kemegahan-
arsitektur-candi-borobudur/ [Accessed 08/10/2013]
- 53 -
Borobudur.tv (2013) Relief Candi Borobudur [WWW] Available from:
http://www.borobudur.tv [Accessed 10/10/2013]
Buddish Art & Architecture (2012) The Temple of Borobudur [WWW] Availeble from:
http://www.buddhanet.net/boro.htm [Accessed 22/10/2013]
Daisetz hoito (1949) The gandavyuha sutra [WWW] Available from:
http://prajnaquest.fr/downloads/BookofDzyan/Sanskrit%20Buddhist%20Texts/
andavyuha_sutra_1949_corrections.pdf tokyo [Accessed 14/0/2013]
Dhiravamsa (2012) Nirvana Upside Down [WWW] Wisdom Moon Publishing LLC,
San Diego. Available from:
http://books.google.co.id/books?id=d9WKrLmJUuYC&printsec=frontcover&h=
id#v=onepage&q&f=fa lse [Accessed 10/10/2013]
Dumarcay, Jacques (1978) Borobudur. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
During, Simon (1992) Foucault and Literature: Towards a Genealogy of Writing
Towards a Genealogy of Writing. London and New York: Routledge.
Fatimah, Titin et al. (2005) BOROBUDUR – RECENT HISTORY OF ITS CULTURAL
LANDSCAPE; Toward the Sustainable Rural Development as the Landscape
Rehabilitation‖ Represented in Forum UNESCO University and Heritage 10th
International Seminar ―Cultural Landscapes in the 21st Century‖ Newcastle
upon Tyne, 1116 April 2005.
Gutting, Gary (2013) ―Michel Foucault", The Stanford Encyclopedia of Philosophy
(Summer 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.) [WWW] Available from:
- 54 -
http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/foucault/ [Accessed
03/10/2013]
Hafizul hamzi (2013) Sejarah Mataram Kuno [Accessed WWW] Available from:
http://www.sibarasok.com/2013/07/sejarah-kerajaan-mataram-kuno-dinasti.html
[Accessed 21/10/2013]
Hariawang, Irma. (2012) Mengulik Teka Teki Candi Borobudur [WWW] Available
from: http://langitselatan.com/2012/08/02/mengulik-teka-teki-candi-borobudur/
[Accessed 14/10/2013]
Haryono, Timbul ( - ) Masyarakat Jawa Kuna dan Lingkungannya Pada Masa
Borobudur [WWW] Available from:
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved
=0CEMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fkonservasiborobudur.org%2Fdownload
%2Fbuku%2FTrilogi%25201%2520100%2520Tahun%2520Pemugaran%2520B
orobudur%2F6_Masyarakat%2520Jawa%2520Kuno_Timbul%2520Haryono.pd
f&ei=wGleUqmZMsLorQfo4YHoBg&usg=AFQjCNFrjDHCs1dFifrDyUJkfga
QTxO4A&sig2=4vvTwrrRHJG3upkZPXj5Qg&bvm=bv.54176721,d.bmk&cad
=rja [Accessed 16/10/2013].
Hayes, Holly (2010) Borobudur [WWW] Available from http://www.sacred
destinations.com/indonesia/borobudur [Accessed 22/10/2013]
HPI Jogja (2013) Lalitavistara [WWW] HPI Jogja (blog) Available from:
http://www.hpijogja.wordpress.com/2010/01/02/lalitavistara/ [Accessed
10/10/2013]
- 55 -
Indonesia Heritage Culture (2012) Ancient Buildings Art: Borobudur Temple [WWW]
Available from: http://natural-heritage-indonesia.blogspot.com/2012/10/the
borobudur-temple.html [Accessed 10/10/2013]
Indonesia Travel (2013) Keajaiban Candi Borobudur [WWW] Available from :
http://www.indonesia.travel/id/destination/233/borobudur [Accessed
29/09/2013]
Indonesia Travel ( - ) Wonderful Indonesia, ‗Membaca Ribuan Panil Relief pada Candi
Borobudur [WWW] Indonesia‘s official tourism website. Available from:
http://www.indonesia.travel/id/destination/233/borobudur/article/202/membaca-
ribuan-panil-relief-pada-candi-borobudur [Accessed 10/10/2013]
Jagad Kejawen ( - ) Candi Borobudur: Temple Discovery And Restoration [WWW]
Available from:
http://www.jagadkejawen.com/index.php?option=com_content&view=article&i
d=22&Itemid=42&lang=en [Accessed 10/10/2013]
Jakarta.go.id (2013) Mercusuar, Politik [WWW] Portal Resmi Pemprov DKI Jakarta.
Available from:
http://www.jakarta.go.id/v2/encyclopedia/detail/1927/Mercusuar-Politik
[Accessed 22/10/2013]
Jan Wisseman, Christie (1982) Patterns of Tradein Western Indonesia: Ninth Through
- 56 -
Kebudayaanindonesia.net ( - ) Candi Borobudur [WWW] Available from:
http://blog.sribu.com/2012/05/04/makna-di-balik-kemegahan-arsitektur-candi-
borobudur/ [Accessed 08/10/2013]
Krom , N.J (2005) Borobudur: An Archaeological Description [WWW] Available from:
http://www.borobudur.tv/mendut_borobudur.htm [Accessed 15/10/2013].
Löffler , Petra (2013) Necsus - Towards a new media archaeology? A report on some
books and tendencies [WWW] Available from:
http://www.necsusejms.org/towards-a-new-media-archaeology-a-report-on -
some-books-and-tendencies/ [Accessed 15/10/2013]
Munandar, Aris Agus (2009) PENGARUH HELLENISME DALAM GAYA SENI ARCA
MASA KLASIK TUA DI JAWA (abad ke-8—10 M) [WWW] Departemen
Arkeologi FIB UI. Acvalable from:
http://www.fib.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=158:p
engaruh-hellenisme-dalam-gaya-seni-arca-masa-klasik-tua-di-jawa-abad-ke-8-
10-m&catid=39:artikel-ilmiah&Itemid=122&lang=in-ID [Accessed 22/10/2013]
Museum Indonesia (2013) Candi Borobudur [WWW] Available from:
http://www.museumindonesia.org/candi-borobudur.html [Accessed 14/10/2013]
Museum of Knowledge (2012) "FOUCAULT‘S HISTORY, ARCHAEOLOGY, AND
GENEALOGY (blog)
http://educationmuseum.wordpress.com/2012/06/01/history-archaeology-and
genealogy/ [Accessed 03/10/2013]
- 57 -
Moens, J.L. (2007) Barabudur, Mendut, Pawon and their mutual relationship [PDF]
[Accesed 20/10/13]
O‘Farrell, Clare (2010) Key Concepts of Michel Foucault [WWW] Available from
http://www.michel-foucault.com/concepts/ [Accessed 09/10/2013]
Pbs.org , nd.( - ) Historical Records Borobudur [WWW]
http://www.pbs.org/treasuresoftheworld/a_nav/boro_nav/bnav_level_1/1historic
al_borofrm.html [Accessed 20/10/13]
Parmono, Atmadi, 1988, Some Architectural Design Principles of Temples in Java: A
study through the buildings projection on the reliefs of Borobudur temple.
Yogyakarta: Gajah Mada University.
PBS (2013) Borobudur-Borobudur: Pathway to Enlightenment [WWW] Available
from: http://www.pbs.org/treasuresoftheworld/borobudur/boro_main.html Press.
[Accessed 15/10/2013]
PNRI (2013) Candi di Indonesia [WWW] Available from:
http://candi.pnri.go.id/pengantar/ [Accessed 27/09/2013]
P S. Bambang (2000) Studi Isu Arkeologi pada candi Borobudur: Perpustakaan Balai
Konversi Borobudur [WWW] Available from:
http://lib.konservasiborobudur.org/index.php?p=show_detail&id=470 [Accessed
15/10/2013]
Root Institute (2013) Bodhgaya Stupa History [WWW] Available
http://www.rootinstitute.com/bodhgaya-stupa/bodhgaya-stupa-history.html
[Accessed 01/10/2013].
- 58 -
Root Institute (2013) The Mahabodhi Temple of Bodhgaya [WWW] Available from:
http://www.rootinstitute.com/bodhgaya-stupa/bodhgaya-stupa.html [Accessed
01/10/2013]
Rouse, Joseph (2005) Power/Knowledge in Gary Gutting, ed., The Cambridge
Companion to Foucault, 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Stupa.org (2013) Mahabodhi Temple [WWW] Available from:
http://www.stupa.org.nz/stupa/mahabodhi/mahabodhi.htm [Accessed
03/10/2013]
Sharp, Daniel (2011) Foucault‘s Genealogical Method [WWW] Available from:
http://philforum.berkeley.edu/blog/2011/10/17/foucaults-genealogical-method/
[Accessed 09/10/2013]
Tanudirjo, Daud Aris ( - ) ―BOROBUDUR YANG INSPIRATIONAL― [WWW] Jurusan
Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Available from:
http://arkeologi.fib.ugm.ac.id/old/download/1179813599JOGGAL_Diskusi_Dad
paper.pdf [Accessed 22/10/2013]
Thirteenth centuries AD.Disertasi, London: School of Oriental and African Studies.
UNECSO (2013) Unesco - World Haritage List: Borobudur Temple Compounds
[WWW] Available from: http://whc.unesco.org/en/list/592 [Accessed
5/10/2013].
- 59 -
Voute, Caesar. E. L, Mark (2008).Borobudur Prymaid of the Cosmic Buddha [WWW]
Available from: http://www.borobudur.tv/book_promo.htm [Accessed
15/10/2013]
Wihara.com ( - ) Bodhisattva Avalokitesvara dalam Gandavyuha Sutra [WWW]
Available from: http://www.wihara.com/forum/mahayana/15092-bodhisattva-
avalokitesvara-dalam-gandavyuha-sutra.html [Accessed 14/0/2013]