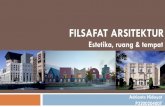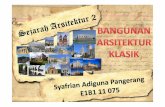paradigma dalam berteori arsitektur
-
Upload
malikusssaleh -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
Transcript of paradigma dalam berteori arsitektur
PARADIGMA DALAM BERTEORI ARSITEKTURPerkembangan perancangan arsitektur sejak era pra-
klasik dan sesudahnya mempelihatkan adanya pergeseran dalamessensi paradigmanya yang dapat digunakan sebagai sumberbertema dan berteori dalam arsitektur.
Pada era peradaban kuno (ancient world) konseparsitekturnya mendasar-kan inspirasinya dari alam semesta yangberkaiatan dengan nilai-nilai kosmos dan mitos.
Pada era kebesaran arsitektur Klasik Eropa (Yunani–Romawi–Renaissance) paradigma arsitekturnya sangat dititikberatkan pada estetika bangunan. Proporsi, simetri, geometridan ornamentasi merupakan sasaran essensial dalam konsepnya,sedangkan aspek struktur dan fungsi berperan minor.
Dengan munculnya gerakan arsitektur modern yang melawankemapanan arsitektur klasik eropa yang doktriner, konseparsitekturnya bergeser lagi dalam paradigmanya.
Perancangan modern mendasarkan pemikiran perancangannyapada paradigma Rasionalisme dimana pertimbangan-pertimbanganperancangannya berdasarkan pada logika dan rasio, menggunakanteknologi baru dan aspek-aspek struktur serta fungsi menjadidominan. Sementara estetika mendapat interpretasi baru denganmengutamakan ekspresi sistem bangunan, struktur dan fungsi.Penyelesaian façade dengan garis-garis linier dan bentukkotak. Assosiasi dengan konteks terabaikan dan eksesnyamelahirkan konsep bentuk yang universal.
Pada pertengahan tahun 1960-an paradigma arsitekturmodern ini mulai dipertanyakan dan ditantang dengan munculnyabuku Complexity and Contradiction in Architecture dari RobertVenturi (19--). Gerakan perbaharuan ini menamakan dirinyasebagai post-modernisme (istilah dari Charles Jenck dalambukunya The Language of Post-Modenism, 1979). Gerakan Post-Modernisme ini menentang azas-azas yang bersifat tunggal atau„universalism‟ dan „uniformity‟.
Kalau gerakan Modern menolak sejarah arsitektur Eropa,kaum post-modernism justru mau merangkul sejarah. Pelbagaiteori bermunculan, paradigma-paradigma teoritik menjadipenentu post modernisme, termasuk teori-teori dari luardisplin arsitektur. Dengan demikian suatu era baru dalamperjalanan sejarah arsitektur modern telah lahir.
Beberapa contoh paradigma yang tersebut diatas merupakanbeberapa diantara paradigma-paradigma yang dianggap gayutdalam perjalan teori arsitektur. Sedangkan masih banyak lagiparadigma-paradigma di dalam belahan bumi yang tidak disebut,baik di Timur maupun di Barat yang berperan sebagai acuan atauinspirasi dalam berkonsep dan berteori.
1. PARADIGMA MITOLOGI dan KOSMOLOGI
Anton Bakker dalam bukunya „Kosmolgi & Ekologi – Filsafattentang Kosmos sebagai Rumah Tangga (1995) mengatakan :
“Kosmologi menyelidikai dunia sebagai suatu keseluruhanmenurut dasarnya. Kosmologi bertitik pangkal padapengalaman mengenai gejala-gejala dan data- data. Akantetapi gejala-gejala dan data-data itu tidak ditangkapdalam kekhususannya, tetapi langsung dipahami menurutintinya dan menurut tempatnya dalam keseluruhan dunia”.
Sedangkan YB. Mangunwijaya dalam bukunya Wastu Citra(1988) :
“Segi mitos dan keagamaan menyangkut ke-ADA-an manusiaatau semesta dari dasar- dasarnya yang paling akar,paling menentukan, paling sejati”.
“Pada tahap primer orang mulai berpikir danbercita rasa dalam alam penghayatan kosmis dan mitis,atau agama. Tidak Estetis”.
Estetis disini artinya penilaian sifat yang dianggapindah dari segi kenikmatan.
Berdasarkan paradigma-paradigma mitis dan kosmologiskeindahan bentuk-bentuk arsitektural bangunan yang terbentukpertama-tama terjadi bukan karena keindahan semata, tetapikarena adanya tuntutan keagamaan atau penyembahan kepadakosmos (alam semesta raya/yang agung). Asas-asasrohanialah yang menghendaki bentuk tersebut, demi keselamatanatau ada-diri daerah, khususnya keluarga-keluarga yangbersangkutan.
Seperti pada orang yang melakukan pertunjukan wayangkulit di Jawa Tengah atau tarian Kecak di Bali. Dari motivasidan suasana aslinya, pertunjukan wayang atau tarian kecakmelulu dilakukan sebagai penunaian kewajibankepercayaan/keagamaa, demi keselamatan diri dan keluarga ataumasyarakat. Dengan sebutan lain: mitologis. Dan pada saat inipertunjukan wayang kulit dan tarian kecak banyak dilakukanhanya untuk konsumsi komersial untuk pariwisata, bukan dalamarti mitologis.
Dalam alam pikiran mitologis, manusia masih menghayatidiri tenggelam di dan bersama seluruh alam dan alam gaib.Belum ada pemilahan antara sang Subyek dan Obyek, menurut YBMangunwijaya dalam bukunya Wastu Citra (1988). Raja merasadirinya titisan dari Dewa Wishnu. Kesuburan Wanita, sawahladang, sesaji Dewi Sri, merupakan perkaara satu, tumbuhanrotan dianggap perpanjangan usus-usus manusia. Bentuk-bentuk meru di Pulau Bali tidak terlepas dari penggambaranbentuk Gunung Mahameru (Konsep Bhuwana Alit & Bhuwana Agung).Rumah-Rumah tradisional Jawa yang dibangun dengan menggunakankeseimbangan atau keharmonisan antara manusia dengan YangMaha Kuasa, Manusia dengan alam semesta (moncopat,kolomudheng, ponco sudho, papat keblat kalima pancer)
(Roemanto, 1999). Piramida dan Spinx di Mesir, dibuat karenaadanya penyembahan dan penghargaan kepada Raja-raja Mesir(Firaun) pada masa itu, yang dianggap sebagai “Tuhan‟ yangpatut disembah.
Penghayatan adanya suatu „pusat dunia‟ atau poros, axismundi, atau pusat, sentrum, caput mundi, merupakan penghayatanmanusia berjiwa religius yang sangat dalam. Manusia tidakdapat hidup dalam angkasa kosong atau ruang homogen,seolah-olah segala titik dan arah itu sama saja. Iamembutuhkan orientasi, pengkiblatan diri. (Mangunwijaya,1988). Sebagai contoh adalah orientasi kepada matahari(orientasi Timur ke Barat), begitu kuatnya perasaanorientasi kepada matahari yang terbit dari timur ke barat,banyak bangsa yang percaya bahwa matahari adalah sumber segalasumber kehidupan. Bila ada timur dan barat, tentunya pulaadapula utara dan selatan, keempat poros inilah menimbulkansuatu titik imajinasi tugu poros, pusat yang tejadi karenapersilangan Utara-Selatan dan Timur Barat.
Konsep Vastu-Purusha-Mandala
Dalam buku Wastu Citra dikatakan bahwa suatu wilayahtidak hanya dipahami geografisnya saja, tetapi seperticontohnya di India, sebagai suatu Mandala, yang berarti bentuk(form). Tetapi merupakan bentuk yang berdaya gaib. Denganhubungan tertentu mendala juga berarti citra gaib ataudaerah kerja energi dan pengaruh kekuatan-kekuatan gaib.Dalam Mandala ada tempat yang paling berdaya, yaitubagian pusar/poros. Dan setiap bagian daerah bangunanmemiliki nilai gaibnya menurut susunan daya mandala tadi.Oleh karena itu seluruh tata wilayah dan tata pembangunanmenurut orang-orang India Kuno harus diarahkan menurut tataVastu- Purusha-Mandala (Vastu = norma dasar semesta yangberbentuk dan berwujud; purusha = insan atau personifikasigejala semesta dasar yang awal, asli, utama, sejati). Dengandemikian dapat dikatakan bahwa bagi orang-orang India dahulu,tata wilayah dan tata bangunan atau arsitekturnya tidak
diarahkan pertama kali demi penikmatan rasa estetikabangunan, tetapi terutama demi pelangsungan hidup secarakosmis, artinya selaku bagian integral dari seluruh kosmosalam semesta raya yang keramat dan gaib. Keraton-keraton diJawa misalnya menempati pusat dari sumbu- sumbu magis, keratonmenjadi patron pusat-pusat pemerintahan yang lebih kecil,tetapi tidak boleh disamai karena ke-binathara-an atau ke-dewa-annya (ratu). Ratu adalah Dewa, menandai penerapan konsepDewa Raja.
Konsep Tribuwana
Masih dari YB. Mangunwijaya dalam bukunya Wastu Citra(1988), pada masa- masa dahulu, masyarakatnya telah membagidunia dalam tiga lapis, dunia atas (surga, kahyangan), duniabawah (dunia maut) dan dunia tengah (dunia yang didiami olehmanusia). Tata bangunan atau wilayah di Dunia Keil kita inipertama-tama harus merupakan cermin pewayangan Dunia BesarSemesta Raya. Mikro-kosmos selaku karo-kosmos yangmengejawantah. Oleh karenanya dalam wujud bangunan selalumempunyai beberapa citra dasar, misalnya bentuk Gunung. Gunungselalu dihayati sebagai tanah tinggi, tempat yang paling dekatdengan Dunia Atas. Candi-candi Hindu dan Budha dibentuk jugakarena adanya penyembahan kepada alam semesta raya (Sang HyangWidhi/Tuhan).
Dari konsep-konsep diatas tampaklah bahwa bagaimanasetiap karya bangunan merupakan upaya penghadiran Semestaatau Kahyangan Raya. Oleh karena itu proses karyapembangunan juga merupakan penghadiran pencipaan Semesta Raya,pewayangan kembali awal mula dunia ketika dijadikan olehDewata atau Tuhan.
Teori-teori/Tema yang berkembang
Dari Buku “Kosmolgi & Ekologi – Filsafat tentangKosmos sebagai Rumah Tinggal‟, (Bakker, 1995) dirinci adanyabeberapa tema yang berkembang dalam paradigma mitologi dan
kosmologi ini. Berikut ini rinciannya yang dibagi berdasarkanpemilahan regional.
Kosmologi Indonesia
Terdapat kesatuan besar antara para penghuni kosmos,seluruh kosmos dirasuk (dijiwai) oleh suatu „zat kejiwaan‟atau daya hidup, atau kesaktian, zat atau daya hidup itu nonpersonal dan pada dasarnya tidak berbeda untuk manusia, hewan,tumbuhan, membuat mereka keramat. Keharmonisan ini diwujudkandalam bentuk keseimbangan antara manusia dengan masyarakatnya,alamnya dan Yang Maha Kuasa. (Roesmanto,1999).
Kosmologi India
Hindu berdasarkan kitabnya Upanishad (ab. 7 – 3 SM) dandalam Vedanta (700 – 1400), dunia mempunyai adanya dalamBrahmana. Budhisme yang dibawa oleh Gautama Siddharta (563 –483) menganggap dunia dan manusia bersatu dalam“kekosongan‟.
Jaina (pendiri Vardhamana 540 – 468) percaya bahwakenyataan terdiri dari dua macam yang berbeda secara radikal.Substansi-substansi yang bukan berjiwa (ajivas) terdiri dariatom-atom, semua sama saja dan tidak bersifat apapun.
Kosmologi Barat
Spinoza (1632 – 1677) percaya bahwa dunia dan manusiakelihatan sebagai substansi-substansi yang berdikari, tetapisebenarnya hanya satu substansi saja, yaitu Tuhan (seringdikatakan sebagai pantheisme).
Hegel (1770 –1831) mengatakan bahwa pada dasarnya manusiadan dunia (alam) adalah fase dan bagian dalam prosespenjelmaan Roh Mutlak (Geist). Dalam lingkup manusia tidak adalagi yang alami, semuanya telah diangkat oleh kerohanianmanusia menjadi budaya (Roh Obyektif).
Sementara Karl Marx (1818 – 1883) menganggap bahwa duniadan manusia lahir dari satu realitas terakhir, materi.
2. PARADIGMA ESTETIKA
Estetika pada awalnya merupakan salah satu cabang ilmufilsafat, tetapi dalam perkembangan kemudian membuat estetikatidak lagi hanya bercorak filsafat tetapi sudah berkembanglebih luas. Pendapat yang sangat berpengaruh namun salingbertentangan perihal pengungkapan keindahan adalah pandangandari sudut teori obyektif dan teori subyektif.
Teori Obyektif berpendapat bahwa keindahan adalah sifat(kualitas) yang memang telah melekat pada bendanya (yangdisebut) yang merupakan obyek. Ciri yang memberi keindahan ituadalah perimbangan antara bagian-bagian pada benda tersebut,sehingga asas-asas tertentu mengenai bentuk dapat terpenuhi.
Teori Subyektif mengemukakan bahwa keindahan itu hanyalahtanggapan perasaan dalam diri seseorang yang mengamati bendaitu. Jadi kesimpulannya tergantung pada penyerapan/persepsipengamat yang menyatakan benda yang dimaksud itu indah atautidak.
Bangsa Yunani misalnya, sangat peka terhadapkeindahan obyektif seperti terlihat pada karya-karya zamanYunani Kuno. Teori agung tentang keindahan (The Great Theoriof Beauty) menerapkan matematika arsitektur Yunani yangdikenal dengan istilah Perbandingan Keemasan (Golden Section).
Perwujudan estetika dalam kaitan keindahan sebagai nilaiintrinsik (sifat baik suatu benda), dinyatakan dengan prisip,kaidah-kaidah keselarasan, keseimbangan dan lainnya. Untukmewujudkan ini digunakan unsur-unsur garis, bentuk, totalitas,warna, tekstur, struktur masa dan ruang.
Bentuk sangat berarti dalam penampilan estetika dimanaperwujudannya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranyaadalah simbol atau lambang sebagai elemen dekorasi. Sejak lamamanusia memerlukan identitas baik bagi dirinya maupun bagibenda-benda yang ada disekelilingnya. Di dalam dunia
arsitektur pengenalan simbol merupakan suatu proses yangterjadi pada individu maupun masyarakat. Melalui pancaindera (dalam hal ini indera penglihat lebih banyak berperan)manusia mendapat rangsangan yang kemudian menjadi pra-persepsidan terjadi pengenalan terhadap obyek (fisik) selanjutnyaterwujud persepsi, dan persepsi ini sangat dipengaruhi olehpengalaman termasuk pengalaman pendidikan yang menentukantingkat intelektual manusia.
Pada hampir dua ribu tahun yang lalu arsitek Roma (Itali)Vitruvius mengemukakan tiga faktor utama dalam arsitektur:venustas, utilitas dan firmistas. Pada permulaan abad ketujuhbelas, penulis Inggris Sir Henry Wotton menterjemahkannyamenjadi “commodities”, firmness dan delight” yangkemudian menjadi sebuah ungkapan yang telah lama digunakansehingga hampir menjadi suatu klise. Ketiga faktor ini selaluada dan selalu berhubungan satu dengan lainnya secara timbalbalik dalam suatu struktur yang baik. Secara naluriah bahwaapapun yang ditentukan terhadap salah satu darinya makalainnya akan terpengaruh.
Paradigma Estetika mendorong tiga prinsip dari Vitruviusdan Henry Wotton pada sisi „venustas‟ dan „delight‟-nya. Diera Yunani dan Romawi, venustas dijabarkan dalam teori-toeriestetika. Yang paling berkembang dimasa ini adalah TeoriProporsi. Dimasa Renaissance, ditambahi dengan penemuan TeoriPerspektif. Bila di Barat ada perkembangan perspektif ini, diTimur berkembang suatu genre geometri yang dikenal sebagai„Arabesque Geometri‟. Namun kemudian estetika menjelma menjadiornamentasi (yang bahkan berlebihan) seperti di era Barok(Baroque) dan Rokoko (Rococco). Dimasa yang lebihkontemporer, bosan dengan ornamentasi, delight,menginspirasi untuk melawannya.
Kemudian teori-teori estetika mendapat tambahan dariteori-teori geometri dan matematika yang melahirkan bentuk-bentuk murni dari tuntutan struktural namun yang sangat indahdan kaya dengan permainan geometri.
Sebagai pengaya, berikut diuraikan beberapa langgamyang berkembang sebagai akibat dari penggunaan paradigmaestetika dan teori-teori yang berkembang pada masa-masaklasik.
Yunani
Pada masa Yunani Kuno karya -karya arsitektur yangdikenal dengan langgam Klasik, terdiri dari balok-balok dankolom-kolom batu. Ekspresinya tampak pada derertan tiangseperti pada Basilika St. Petrus di Roma, kuil Parthenon danbangunan lainnya di Arcopolis dekat Athena.
Sebagai tiang penyangga terdapat tiga jenis kolom yangcukup berperan dalam perwujudan bangunan arsitektur Yunanidengan istilah Dorik Ionik dan Korintian. Kolom Dorikmempunyai tampilan yang terkesan jantan kokoh dan kaku,sedangkan Ionik dan Korintian lebih terkesan feminin, luwes,ornamental dengan dimensi yang lebih langsing. Tetapi secarakeseluruhan, paradigma Estetika dalam arsitekturnya lebihessensial, yang sarat oleh kaidah-kaidah dan norma-norma “TheGraet Thoery of Beauty” dan “Golden Section”.
Romawi
Munculnya Kekaisaran Romawi di Italia mempunyai dampakterhadap nilai-nilai budaya dan karya-karya arsitektur didaerah dan wilayah kekuasaannya. Gaya atau langgam ArsitekturRomantis, mempunyai ciri yang berbeda dengan langgamarsitektur Yunani Kuno, ditandai dengan bentuk-bentuk lengkungbusur lingkaran pada struktur bagian atas bangunan, dansecara keseluruhan terkesan tidak sehalus arsitekturlanggam Yunani Kuno.
Sejalan dengan meluasnya daerah kekuasaan Romawi padamasa kejayaan Kaisar Constantin ke daerah Timur,Konstantinopel di Turki menrupakan pusat wilayah kekuasaanyadi daerah Timur, dan di wilayah tersebut berkembang budayaRomawi dengan berbagai aspeknya termasuk arsitektursebagai unsur budaya yang berasimilasi dengan budaya
yang memunculkan corak Bizantium. Paradigma Estetika dalamarsitektur Romantis masih sangat mendominasi.
Gothic
Tahap perkembangan arsitektur berikutnya setelah eraRomawi dalam arsitektur Kristen tertanam dalam kathedralGothic. Ciri yang sangat menonjol dari arsitektur Gothictercermin pada struktur lengkung bersudut pada puncak sebagaiupaya untuk mendapatkan proporsi antara ketinggian denganbentang yang dikehendaki.
Dalam arsitektur Gothic meskipun struktur sudahmerupakan pertimbangan dalam perancangan khususnya padastruktur atas bangunan, tetapi dalam penyelesaianarsitekturnya, paradigma estetika justru sangat dominan,dimana struktur lengkung runcing dikamuflir dengan ornamen-ornamen vertikal menjulang tinggi.
Ide yang diekspresikan dalam bangunan ini merupakan jiwa,roh absolut, bilik dalam Tuhan. Untuk pertama kalinya dalamteori Estetika, ruang dalam yang sekarang terlingkung dalamsuatu batas arsitektural, dipahami diidentifikasikan sebagaiisi yang diperlukan (Ven, 1974).
Renaisance
Langgam Renaisance dalam arsitektur muncul padaera Renaisance (pembaharuan) yang diawali setelahrevolusi humanis, dengan landasan berpikir bahwa manusiamempunyai kedudukan sejajar. Sejalan dengan pola pikir padamasa Renaisance sebagaimana dikemukakan diatas, konseparsitekturnya mengacu kepada prinsip-prinsip garis horizontal,dengan menanggalkan vertikalisme yang merupakan konseparsitektur Gothic.
Kendati dalam era Renaisance ada pergeseran pola pikirdalam konsep arsitekturnya namun paradigma Estetika tetapmendominasi perwujudannya. Façade bangunan penuh denganornamen-ornamen non fungsional bila ditinjau dari fungsi
bangunannya, dan ornamen tersebut semata-mata dimaksudkansebagai pendukung paradigma Estetika. Langgam Baroc dalamarsitektur merupakan penonjolan kedudukan paradigma Estetikadari konsep-konsep dalam langgam sebelumnya. Tampilan bangunanmenjadi sangat dekoratif yang penuh dengan ornamen-ornamen nonfungsional, sedangkan gaya Rococco merupakan perwujudanarsitektur bangunan ornamentalis yang berlebihan.
3. PARADIGMA SOSIAL (HUMAN SCIENCE)
Manusia seperti diketahui termasuk mahluk sosial. Manusiatidak dapat selamat dengan hidup menyendiri. Dari lahir hinggamulai belajar, lingkungan yang dihadapinya adalahlingkungankeluarga terutama ibu dan ayahnya yang disebut keluarga batin.Kemudian membentuk masyarakat. Demikianpun semakin besar dantentu saja semakin kompleks. Beberapa cerminan interaksisosial yang terwujudkan dalam arsitektur.
Semangat kerjasama di dalam hal ideologi. Kita bolehberbangga hati dan kagum jika melihat megahnya candiBorobudur, candi Prambanan, sebagai karya arsitektur dan lain-lain peninggalan nenek moyang kita jaman duhulu hingga saatini masih tetap berdiri dengan megahnya. Seperti diketahuiagama Budha berasal dari India yang datang ke Indonesia dibawaoleh pedagang sambil berdagang mereka mengembangkan agamabudha dan interaksi dengan masyarakat setempat terjadilahakulturasi agama kedalam masyarakat tanpa mengubah adatistiadat yang telah ada. Dengan adanya agama Bbudha merekamembutuhkan prasarana peribadatan dan didirikanlah candi-candi.
Candi-candi inilah yang merupakan karya arsitektursebagai perwujudan dari adanya interaksi sosial dalam bentukkerjasama dan akulturasi budaya masyarakat pendatang danmasayarakat yang ada, yang dalam perwujudannya berdampingandengan bangunan tempat tinggal penduduk dengan ciri arsitekturtradisional setempat.
Persaingan. Pada dasarnya manusia selalu berkeinginandihargai dan hidup dengan lebih baik. Namun ini merupakanpendorong utama dari dalam diri manusia yang mengakibatkanterjadinya apa yang disebut urbanisasi yaitu perpindahanpenduduk dari desa ke kota.
Dengan adanya urbanisasi ini terjadilah interaksi sosialdalam bentuk persaingan dan terjadi peningkatan kebutuhansarana dan prasarana permukiman dikota khususnya bagimasyarakat pendatang yang umumnya orang-orang miskin dengantingkat pendidikan relatif sangat rendah.
Untuk memnuhi kebutuhan inilah mereka membangun melaluiproses persaingan tanpa mengikuti peraturan yang adadengan bahan seadanya dan dengan penyelesaian tanpateknologi yang dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai akibatnyatimbul permukiman kumuh didalam lingkungan kota yang dilainpihak tertata permukiman yang rapi, baik dan teratur yangmerupakan tantangan bagi penentu kebijaksanaan pembangunankota dalam penanggulangannya.
Dalam beberapa hal misalnya seorang yang mengalami cacat,bahkan perlu didampingi sepanjang hidupnya, Selama prosesmembesarkan anak-anaknya atau mendampingi seseorang itulahmanusia membutuhkan berbagai bentuk pedoman atau aturan-aturanyang disepakati.
Manusia adalah mahluk bersikap atau memilih. Alammenyediakan kemungkinan-kemungkinan dan manusia menjatuhkanpilihan-pilihan yang dipandang dapat menguntungkan.
Kluckholn menyatakan bahwa komunitas manusiamemiliki sistem-sistem bahasa, ilmu/pengetahuan,paralatan/teknologi, mata pencaharian, masyarakat/ komunitas,kesenian dan sistem religius/kepercayaan. Sistem-sistem itumelukiskan segala upaya manusia untuk tetap selamat ditengahalam dan diantara kelompok- kelompok yang ada. Contohnya,yaitu sistem mata pencaharian merupakan pertemuan antara
manusia dengan alam yang diolahnya melalui seperangkat sistemperalatan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.
Manusia dikatakan juga sebagai mahluk yang menciptakansimbol. Secara akademis tanda dan simbol itu memang dibedakan,namun dalam kehidupan sehari- hari dua hal tersebut memilikiperan dan fungsi yang sama, yakni membawa mereka sama-samabermaksud menyampaikan pesan.
Representasi merupakan ungkapan bahasa yang sangatpenting didalam arsitketur, dia mengubah dari suatu gagasankedalam suatu wujud yang nyata dengan pertimbangan syarat-syarat subyektif dan obyektif tertentu. Penyampaian gagasanmelalui tanda-tanda atau simbol-simbol selalu berlangsungdalam konteks sosial. Bahasa asitektur akan berfungsidengan baik hanya apabila disertai denga kesepakatansubstantif maupun representatif. Kesepakatan sosial merupakankunci bagi berlangsungnya suatu bentuk komunikasi.Untuk dapat mencapai paras komunikatif, arsitekturmembutuhkan penerimaan sosial. Sebagai contoh yang dapatdisampaikan ialah penggunaan bahan batu kali atau batu alamlainnya untuk bentuk/konstruksi pondasi batu atau dinding yangmasif, dapat memberikan ciri atau tanda yang kokoh.
Arsitektur Adalah Cerminan Kebudayaan
Arsitektur sebagai suatu karya kesenian hanya bisatercapai dengan dukungan masyarakat yang luas, berbeda dengankarya seni lukis atau seni patung yang bisa terlahir hanyadengan usaha satu orang seniman saja.
Untuk melahirkan karya arsitektur diperlukan selainarsitek, juga ahli-ahli teknik lain, industri bahan,sekelompok pelaksana, teknologi dan lain-lainnya. Olehkarenanya patutlah dikatakan bahwa arsitektur adalahpengejawantahan dari kebudayaan manusia. Atau dengan katalain arsitektur selalu dipengaruhi kebudayaan danmasyarakatnya.
4. PARADIGMA RASIONALIS
Pengertian istilah ini, menurut Kamus Advanced English –Indonesia adalah sebagai berikut: Rationale yang berarti(1)alasan utama (2)dasar alasan. Sementara Rationalismdiartikan sebagai prinsip atau kebiasaan untuk menerimapenalaran sebagai kekuasaan tertinggi dalam hal mengemukakanpendapat. Rationalist adalah orang yang menerima penalaransebagai kekuasaan tertinggi.
Dalam dunia arsitektur, Rationalisme diartikan suatuparadigma dalam arsitektur yang didasarkan pada hal-hal yangbersifat nalar. Atau dapat dikatakan sebagai suatu cara untukmencetuskan ide-ide arsitektur yang didasarkan padapertimbangan yang masuk akal.
Paradigma Rasionalis tumbuh pada sekitar pertengahan abadXIX di Eropa, Hal ini merupakan jawaban atas kondisi yangterjadi pada saat itu. Adapun penyebabnya adalah (a) munculnyarevolusi industri yang ditandai dengan munculnya teknologikonstruksi. (b) meningkatnya kebutuhan rumah tinggal di kotakarena pesatnya arus urbanisasi dan (c) semakinmeningkatnya bentuk-bentuk eklektis dalam karya arsitektursaat itu, yang tidak sesuai dengan perkembangan teknologi.
Tokoh-tokoh Arsitek penganut Rasionalisme
Prinsip-prinsip rasionalisme dianut antara lain oleh tokoh-tokoh seperti : Walter Gropius, Ludwig Meis van Der Rohe, danLeCorbusier. Contoh-contoh bangunan yang menjadi simbol dariparadigma rasionalis adalah Kampus Bauhaus karya WalterGropius, Apartemen LeUnite de Habitation di Mersaillesdan rumah tinggal Villa Savoye, keduanya karya LeCorbusier.Di Amerika diwakili oleh Crown Hall di Chicago dan Seargram diNew York karya Ludwig Meis van Der Rohe.
Paradigma rasionalisme pada karya arsitektur mempunyai ciri-ciri sebagai berikut
fungsi sebagai penentu bentuk dan ekspresi,
struktur bangunan menjadi bagian dari estetika baru, ornamen-ornamen yang tidak perlu dihilangkan dan prinsip perancangan menjadi universal yang mengakibatkan
lahirnya gaya internasional (International Style) denganakibat aspek konteks terabaikan.
Semboyan-semboyan pada paradigma rasionalis
Paradigma rasionalis memunculkan semboyan-semboyan daritokoh-tokoh arsitektnya yang merupakan dasar falsafah bagikarya-karya mereka. Semboyan tersebut antara lain :
Form Follow Function. Semboyan ini dicetuskan oleh Louis Sullivanyang mendefinisikan arsitektur analog dengan bentuk alam atausebagai ekspresi suatu gaya hidup batin dan logika strukturmanusia. Bentuk merupakan turunan dari fungsi yang berartifungsilah yang menciptakan dan mengorganisir bentuk. BagiSullivan fungsi bukanlah suatu program bangunan yang mati,melainkan kehendak hidup yang mendiami substansi, seperti yangmendiami si seniman pencipta (Ven, 1967).
Less is More. Merupakan semboyan yang dicetuskan oleh Ludwig Meisvan Der Rohe yang intinya adalah dalam bentuk yang palingsederhana. Arsitektur berakar pada pertimbangan-pertimbanganestetika yang essensial, namun arsitektur dapat menembussegala tingkatan derajat nilai samapai mencapailingkungan tertinggi eksistensi spiritual, kedalaman khasanahseni murni (Ven, 1967).
Un Machine d’habiter. Machine for Living, merupakan formulaLeCorbusier yang artinya rumah adalah mesin untuk bermukim.Aspek positif dari perumusan LeCorbusier itu ialahkesadaran bahwa dalam dunia bangunanpun efisiensi,rendemen, ekonomi, harus dicapai semaksimum mungkin sepertidalam perekayasaan setiap mesin (Mangunwijaya, 1988).
Paradigma Rasionalis pada berbagai zaman
Paradigma rasionalis tidak hanya terdapat pada zamanarsitektur modern, tetapi menurut Mangunwijaya telah dapat
kita lihat pada zaman Yunani maupun pada arsitekturtradisional di berbagai tempat di dunia.
Arsitektur Yunani
Orang Yunani selalu rasional. Mereka selalu berfikirtentang hakekat sesuatu. Dalam arsitektur pun mereka mencarihakekat bangunan itu dan mencoba mengungkapkannya dalambentuk. Mereka berpendapat bahwa segala bangunan berhakikatdua prinsip yaitu :
1. ada unsur yang ditopang dan 2. ada unsur lain yang memikul atau menopang.
Bila diantara yang dipikul dan memikul ada keseimbanganartinya serba stabil, maka hakekat sudah tertemulah dan justruitulah yang harus diekspresikan (Mangunwijaya, 1988).
Arsitektur Tradisional Jepang
Jika kita amati arsitektur tradisional Jepang sangatdekat dengan paradigma rasional. Tanda-tanda ini dapat kitalihat pada ciri-ciri arsitektur Jepang seperti dinding-dindinggeometrik, bentuk serba polos atau tidak ada hiasan dan sistemstruktur yang sesuai dengan logika. Perumusan seperti yangdiungkapkan oleh Meis van Der Rohe “Less is More”, telah lebihdahulu berabad-abad dikerjakan oleh orang Jeapang(Mangunwijaya, 1988).
5. PARADIGMA KULTUR
Kegiatan dalam mewujudkan karya-karya interaksi ruang,makna, komunikasi dan waktu yang berfokus pada penataanlingkungan. Penyebab penting dalam penataan tersebut adalahbahwa makna lingkungan didalamnya membantu komunikasi sosialantara orang-orang dengan lingkungan kepada masyarakat melaluikultur masing-masing. Jadi lingkungan melalui ruang dan maknamencerminkan pengaturan komunikasi, sebab komunikasi merupakanfaktor penting bersifat temporal dan dapat dianggap pengaturan
waktu. Waktu bisa masa lampau, sekarang dan yang akandatang.
Essensi
Pengejawantahan gagasan pengaturan interaksi ruang,makna, waktu dan lingkungan; pertama-tama mengacu kepadaalam dengan muatan spiritualis/ religiusitas yangkental, berlandaskan kesadaran yang cair sehingga cenderungberubah dari waktu ke waktu. Perbedaan antara kultur di Baratdan kultur di Timur secara garis besar adalah Barat inginmenguasai alam, sedang Timur ingin menyelaraskan denganalam. Kultur Barat didominasi oleh pemikiran-pemikiran Yahudidan Kristen sedangkan kultur Timur lebih banyak didominasioleh pemikiran-pemikiran Hindu, Budha di belahan bumi Indiadan Asia Tenggara, bercampur dengan Tao, Lao- Tse, Konghucu dibelahan bumi Cina, Korea dan Indocina, di Jepang bercampurdengan Shinto. Islam sebagai agama terkemudian mempengaruhisebagian besar pemikiran-pemikiran di Mediteranian, Arab,Persia dan sebagian besar Asia Tenggara.
Masa pre-Modern peradaban Barat dengan melihat peradabanmasa kejayaan Roma masa lalu lebih berkembang dan mulaimendominasi peradaban dunia dan menimbulkan pandangan-pandangan Romantisme, dengan semangat Renaissance. Loncatankemajuan yang diawali pada Revolusi Industridengan semangat Renaissance membentuk pandangan yangmemiliki perhatian terhadap logika konstruksi, strukturtersembunyi dalam langgam ornamen. Pada masa itu dimulaipenemuan-penemuan baru dalam konstruksi seperti pre-fabrikasidengan penggunaan material-material baru. Motif sejarah lokalmenguat, kebebasan individual berkembang menimbulkanpendekatan baru pada disain dan individu, material-materialbangunan disintesakan dalam penerapan ornamen dan konstruksi.Kemajuan akibat Revolusi Industri menimbulkan ledakan pendudukdan mendorong penggunaan konstruksi yang tepat serta adaptifdengan mempelajari problem-problem masa lalu. Arsitektur tanpa
bentuk tumbuh dalam dunia yang keras, brutal sehinggamenimbulkan kebebasan visual.
Pada bagian dunia Timur hanya Jepang yang mampumengadaptasi pemikiran- pemikiran Barat pada masa pre-Modern.Unsur-unsur Barat itu diimport, dipelajari, ditiru, diserap,dan kemudian diberi jiwa / kehidupan baru, diperbaiki dandibentuk kembali bentuk akhir yang muncul sebagai elemen yangberkepribadian Jepang. Disini orang tidak bisa lagi membedakanapakah unsur-unsur tersebut berasal dari asing ataukah asliJepang.
Hal tersebut diatas berpengaruh juga pada perkembanganarsitektur Jepang. Prinsip-prinsip arsitektur Barat telahterpinjam dan diserap sedemikian rupa sehingga masyarakatJepang pada umumnya telah menganggap dan menerimanya sebagaibagian dari warisan arsitektur nasional mereka.
Masa modern faham-faham Sosialisme, Komunisme,Kapitalisme, dan Fasisme saling bersaing dalam memperebutkanhegemoni-hegemoni ideologi dan praktek-praktek ekonomi.Pandangan-pandangan tersebut timbul dengan menaruhperhatian pada suasana persaingan ideologi dan persaingansumber baku dan pasar bagi industri- industri mereka.Peradaban Barat menguasai Timur dalam suasana universal,pemanfaat teknologi industri berkembang seiring dengankebutuhan-kebutuhan ekonomi. Harmonisasi antara elemen-elemenmodern dengan perubahan sosial ekonomi berkembang. Kalkulasiwaktu menjadi penting dalam kaitan metodologi membangun yangmemperpadukan kepentingan teknik konstruksi dan teknikekonomi. Karya arsitektur tidak hanya cerminan bentuk saja,tapi sudah merupakan cerminan utilitas, komunitas dankomunikasi bangunan. Karya arsitktur sudah merupakanjaringan kehidupan didalamnya. Fantastisme Futuristik yangpenuh imajinasi tentang pemanfaatan teknologi mengemuka dalamusulan-usulan arsitektur. Di Barat, fantastisme futuristiktetap tinggal fantasi sedang di Jepang memperoleh banyakpengagum sampai memasuki periode Post-modern.
Arsiteknologi, futurisme dan metabolisme adalahketerpaduan yang tuntas antara perkembangan teknologi moderndengan warisan kultural dan arsitektural dengan labelarsiteknologi. Fantasi futurisme lahir karena kemajuanteknologi dan ekonomi telah menciptakan suatu iklim yangmerangsang penggunaan building system yang pre-industrialized, pre-fabricated dan pre-packaged denganpertimbangan utama pada segi-segi ekonomi dan efisiensi sertaberkembang menjadi norma estetio yang disepakati bersama.Metabolisme didasarkan pada analogi organis dalam prosesbiologis untuk pelestarian kehidupan melalui “continuouscycle” dalam pembentukan dan pemusnahan protiplasma. Dalamberarsitektur istilah metabolism adalah penciptaan lingkungandinamis yang dapat hidup tumbuh dengan membuang bagian- bagianyang sudah rusak dan melahirkan elemen-elemen baru yang lebihdibutuhkan. Arsitektur dianggap sebagai jasad hidup yangcapable dalam bereaksi dengan berbagai tingkat perubahanyang terjadi. Salah satu tujuan metabolisme mengembangkansuatu building system yang dapat mengatasi berbagai masalah-masalah didalam kehidupan masyarakat yang cenderung selaluberubah cepat dan pada saat yang sama cenderung melestarikantata kehidupan yang sudah mantap / stabil. Gejala-gejalatersebut diatas jauh lebih kuat terjadi di Jepangdaripada di negara-negara Barat lainnya sebab Jepang negarakepulauan, berpegunungan, kepadatan penduduk tinggi. Keadaantersebut telah merangsang penggalian elemen- elemen kunci yangterutama menyangkut “change ability”, „elasticity” dan“flexibility” yang tanggap terhadap dinamika perubahan.
Konsep Rancangan dan Estetika
Paradigma-paradigma kultur dalam konsep, rancangan danestetika yang melatar belakangi masa-masa pre-modern sampaipost-modern dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :
Konsep Rancangan Estetika
Pre-Modern Modern Post-Modern Masih kental Universal Peka terhadap
dalam tradisikepercayaandan religi.
Penemuan-penemuan barudan kebebasanindividualtapi masihmengadaptasiterhadapproblem-problem masalalu.
Kembali kepadainspirasialamiah.Dimulaiproblemledakanpenduduk.Campuran gayahistoris
Perubahanberarti padamode dan carakebiasaanmasyarakat.
Penerapanpengetahuandan teknologi
Ekspresi padabentuk-bentukalamiah, anti-tesis terhadappenampilangeometris yangteratur.
Pre-fabrikasidimulai
Logikakonstruksi /struktur
Kesederhanaan,kerapihan,ketelitian.Perubahansosial danekonomi
Kesadaran akanpenyesuaianalam danlingkungan
FragmentalismearsitekturTanggap akandinamikaperubahan.Arsitekturadalah analogibiologisMeninggalkanasal daerahdan sejarahPemanfaatanteknologi
Memberikenyamananpsikisdisampingfisik
Hubunganbangunan dankegunaan,ketepatanmaterial dansistemkonstruksi
ElitismeprofesiarsitekturFuturistik danmetabolistikEstetikaarsitektur dan
perubahansejarah danbudayaOrientasi padakeberagamanpandangan dantata nilaiMelebih-lebihkanteknologi
Pendekatanterhadappeubahansejarah danbudaya
Ruang-ruangdan bentuksebagai bahasadan saranakomunikasi
Citra akankesempurnaanteknologi
Perpaduanantarakesatuanfungsi danbentuk dalamkomponen dankomposisi/unity
Estetika mesin Estetika
strukturkonstruksi danbahan.
tersembunyidibaliklanggamornamen.
Menggabungkanmaterial-material baru.
Sintesa logamdan kaca, kayudan penerapanornamen sertakonstruksidalaminspirasiilmiah yangmenakjubkan.
Penataan dankeindahanlingkungan.
fungsi Cerminan
bentuk teknikkonstruksi,teknikekonomi,utilitas dankomunikasi
Arsitektursebagai bahasa
Keserbaragaman untukmenghilangkankesan monotonyang dingin.
Contoh kasus
Di Timur kultur Bali dengan perpaduan akal pikiransetempat dan kaidah-kaidah agama Hindu sangat dominan dalamarsitekturnya. Kaidah-kaidah tersebut secara substansi masihrelevan untuk dikembangkan sampai sekarang.
Kultur Jepang setiap kali memang terkena pengaruh-pengaruh asing dari luar akan tetapi setiap kali itupulalah masyarakatnya merangkum dan mengadaptasi pengaruh-pengaruh tersebut sehingga terserap menjadi kebudayaan merekasendiri.
Sikap khas tersebut berpengaruh dalam arsitekturkontemporer Jepang. Prinsip- prinsip arsitektur Barat yangdipelopori di Eropa dan Amerika pada awal sampaipertengahan abad dua puluh telah dipinjam dan diserapsedemikian rupa oleh masyarakat Jepang sehingga memungkinkanadanya perkembangan dari berbagai macam dan langgam arsitektur
dan juga teknologi modern yang sangat impresif danrevolusioner. Gagasan metabolis arsitek lahir dari empatarsitek dan seorang jurnalis dibidang arsitektur yaitu KishoKurokawa, Fumihiko Maki, Masato Otaka, Kiyonori Kikutake danNoburo Kawazoe.
Gagasan Futuris telah diejawantahkan dengan sedikitperubahan oleh Kiyonori Kikutake pada Expo 70 di Osaka dariFuturis Entertainment-tower karya Peter Cock untuk MontrealWorld Expo 1963.
6. PARADIGMA POST-MODERNISM
(Bagian ini banyak mengutip secara langsung dari JosefPrijotomo yang menterjemahkan buku Theorizing A New AgendaFor Architecture karangan Kate Mesbitt, 1996).
Fenomenologis
Fenomenologis sebagai aliran filsafat ini sering dikatakansebagai dasar dan landasan bagi post-modernisme dalam bersikapterhadap tapak, tempat (place), landscape, dan perbuatanarsitektur. Ahli-ahli teoritisi di era post-modernismemenggunakan fenomenologi “investigasi yang seksama ataskesadaran beserta segenap obyeknya”. Merupakan obyek kajianpara teoritisi tentang ketersambungan antara arsitektur dengantubuh manusia.
Beberapa teoritisi yang melakukan kajian terhadap fenomenologiarsitektur diantaranya :
Husserl, dengan dasar pekerjaan fenomenologinya adalah“investigasi yang seksama atas kesadaran beserta obyeknya”.
Martin Heidegger, dengan kajian fenomenologinya yang sangatpenting untuk diketahui adalah “bangunan (building) ituberbeda dengan hunian (dwelling). Hunian menurut Heideggermengandung makna “tinggal bersama benda” [dengan mengakuibenda sebagai sebuah eksistensi, dan disini dimasukan golongan
benda itu – catatan Josep Prijotomo]. Heidegger juga meyakinibahwasanya bahasa membentuk pikiran-pikiran manusia, sedangkanpikiran dan puitika menjadi tuntutan bagi hadirnya hunian.
Christian Norberg-Schultz, dengan melakukan penafsiran terhadapfenomenologi Heidegger. Mengatakan potensi yang dimiliki oleharsitektur adalah dalam mendukung keberadaan dan kehadirandari hunian (dwelling). Norberg-Schultz memang diakui sebagaipendekar utama dari fenomenologi arsitektur, yang memilikikepedulian yang tinggi tentang “konkretasi yang eksistensial”melalui pembuatan tempat (palce).
Juhanni Pallasmo, banyak menyoroti aprehensi psikis dariarsitektur. Karena itulah dia berbicara tentang „membukacakrawala pandangan terhadap realitas kedua dari persepsi,mimpi, kenangan yang terlupakan dan imajinasi‟.
Linguistik
Restrukturisasi yang berlangsung dalam paradigmalinguistik telah memberikan efeknya bagi kepedulian post-modern terhadap kritik kebudayaan. Semiotika, Strukturalisme,serta Post-Strukturalisme tertentu (termasuk Dekonstruksi)telah mengubah bangun dari (demikian) banyak disiplinpengetahuan, termasuk susastra, filsafat, antropologi dansosiologi.
Pardigma-paradigma baru yang membanjir ditahun 1960-anternyata sejalan pula dengan menggejolaknya perhatian duniaarsitektur dalam menghadirkan kembali makna dan simbolisme.
Para arsitek melakukan kajian bagaimanakah makna “dibawa”oleh bahasa dan mengaplikasikan kajian itu, para arsitekmelakukan kajian itu kedalam arsitektur, dengan melaluijalur „analogi linguistik‟. Dalam kajian itu, para arsitekmempertanyakan misalnya, sejauh manakah arsitektur itubercorak kesepakatan (convention) itu mampu memahamibagaimanakah kesepakan itu menghasilkan makna.
Dalam menetang fungsionalisme modern sebagai sebuah„determinant of form‟, dari sisi tinjauan linguistik dikatakanbahwa obyek-obyek arsitektur itu tidak memiliki makna yanginheren. Makna itu dikembangkan dalam arsitektur melaluikesepakatan budaya (cultural convention).
Semiotika
Teori linguistik diperlukan oleh post-modern dalampenciptaan dan respsi (reception) makna. Dengan menempatkansebagai sebuah sistem yang tertutup, semiotika danstrukturalisme telah banyak berurusan dengan bagaimanakahbahasa itu berkomunikasi?.
Sebagai sebuah sistem tanda (sign) yang memiliki dimensitata susunan (structure) (syntactic) dan dimensi makna(meaning) (semantic), semiotika atau semiologi melakukanpengkajian bahasa dengan ancangan/pendekatan (approach) yangilmiah. Disini pertalian-pertalian struktural mengikat tandadengan komponen-komponennya (signifier/signified) bersama-sama.
Pertalian sintaktik adalah pertalian diantara tanda-tanda. Pertalian semantik yang berurusan dengan makna, yaknipertalian antara tanda-tanda dengan obyek yang disuratkannya(di-denotai-nya). Beberapa asas penting telah dilontarkan olehPierce maupun Ferdinand Saussure.
Sumbangan penting dari semiotika/logi diantaranyaadalah pertama, bahasa dikaji secara sinkronik; kedua, tanda(sign) dalam pengertian linguistik adalah sebuah pertalianstruktural dari penanda (signifier) dengantertanda(signified). Tentu saja, tidak boleh dilupakan adalahgagasan yang mengatakan “bahasa adalah sebuah sistemistilah/sebutan yang interdependen dimana nilai dari setiapistilah/sebutan yang lain” [istilah/sebutan=term – catatanJosef Prijotomo).
Semenjak 1960-an, penerapan teori semiotik ini mampumemasuki disiplin arsitektur. Disini dapat dimunculkan,misalnya saja, pandangan dari Umberto Eco yakni:
Arsitektur dapat dipelajari sebagai sebuah sistemsemiotik mengenai per-tanda-an (signification).
Tanda arsitektural (morpheme) mengkomunikasikan fungsiyang memungkinkan (possible functional) melalui sebuah“sistem sepakatan (convention) dan sistem aturan (code).
Tanda (arsitektural) mendenotasikan fungsi primer danmengkonotasikan fungsi sekunder, bila yang dilakukandisini adalah penerapan literal dari fungsi-fungsiprogramatik.
Ringkasnya semiotika merupakan jalan yang dapatditempuh oleh arsitektur dalam pengkajian arsitektur sebagaisebuah medan kegiatan memproduksi pengetahuan (arsitektur).
Strukturalisme
Strukturalisme merupakan metoda kajian yang meyakinibahwa “hakekat yang benar dari sesuatu benda tidak beradadidalam benda itu sendiri, tetapi didalam pertalian-pertalian diantara benda-benda itu, yang kita bangun(construct) untuk kemudian kita cerap (percieve).
Strukturalisme juga mengatakan bahwa dunia kita iniadalah jagad ke-bahasa- an, yakni sebuah struktur pertalianpenuh makna diantara berbagai tanda arbiter. Dengan demikian,strukturalis menekankan bahwa didalam sistem linguistik ituyang ada hanyalah perbedaan-perbedaan, tanda istila/sebutanyang positif.
Strukturalisme memusatkan perhatian pada aturan (code),sepakatan dan berbagai proses yang bertanggung jawab terhadapinteligibilitasnya (inteligibility). Dengan kata lain,memusatkan perhatian pada “bagamanakah sebuah makna sosialdiproduksi”. Sebagai sebuah metoda, strukturalisme tidakberurusan dengan kandungan-kandungan tematik pertandaan,tetapi dengan kondisi-kondisi pertandaan.
Strukturalisme itu bercorak lintas disiplin (crossdiciplinary) walaupun akarnya adalah linguistik danantropologi. Daya tarik strukturalisme bagi arsitektur dapatditunukan dari kutipan “strukturalis menempatkan linguistiksebagai sebuah model dan berusaha untuk mengembangkan „tata-bahasa‟ himpunan yang sistematik atas unsur- unsur besertasegenap kemungkinan kombinasinya yang akan menentukan wujuddan makna dari suatu karya susastra”.
Post-Strukturalisme
Perbedaan antara strukturalisme dan post-strukturalismedapat ditunjukan lewat pernyataan Hal Foster. Kalaustrukturalisme berurusan dari stabilitas dari komponen-komponen tanda, maka post-strukturalisme bekerja dengankelumatan kontemporer tanda-tanda dan terbebaskannya permainanpenanda-penanda (contemporary dissolution of sign and thereleased play of signifiers). Memang, Rolan Barthes menunjukanbahwa penanda itu memiliki potensi untuk melakukan permainanbebas (free play) dan penundaan tanpa kahir (endless defferal)atas makna-makna. Potensi ini dapat dilihat dari mata rantaimetafora yang tak berhingga banyaknya.
Post-strukturalisme memang boleh saja ditempatkansebagai kritik terhadap tanda-tanda. Lihat saja pertanyaanyang dilotarkannya “apakah tanda itu memang benar hanyaterdiri dari dua bagian (penanda dan tertanda), ataukah diajuga bergantung pada kehadiran dari penanda lain yang tidakdigandeng oleh tanda tadi (mengingat penanda lain itulahyang menentukan adanya perbedaan-perbedaan tanda)” [lihatsja contoh kasus bendera merah putih bendera Monaco danbendera Indonesia. Adakah perbedaan dari Monaco dan Indonesiayang menjadikan merah putihnya Monaco bukanlah merah putihnyaIndonesia. –catatan Prijotomo].
Terry Eagleton lantas mengatakan bahwa strukturalismemembagi tanda dari sisi pengacu (referent – the object referedto), sedang post-strukturalisme melangkah lebih lanjut, yaknimembagi penanda dan tertanda yang masing-masing adalah sebuah
entitas mandiri. Akibatnya, makna-makna tidak denganserta merta hadir dalam sebuah tanda. [makna itu dihadirkan– catatan Josef Prijotomo].
Dekonstruksi
Dekonstruksi merupakan salah satu manifestasi post-strukturalisme yang paling benar (significant). Sebagaisebuah praktek filsafat dan linguistik, dekonstruksimelakukan pengamatan kritis terhadap dasar-dasar pemikiranlogo-centrisme maupun disiplin-disiplin pengetahuan/keilmuanseumumnya.
Derrida mengatakan: “dekonstruksi menganalisa danmempertanyakan segenap pasangan-pasangan konseptual(conceptual pairs) [betul/salah, elite/proletar-jp] yangselama ini diterima sebagai kenyataan yang alamiah dan takperlu penjelasan karena sudah jelas, sepertinya pasangankonseptual itu tak pernah dilembagakan pada suatu waktu yangtertentu karena sudah dipandang cukup jelas, tidak disadaribahwa pasangan konseptual ini menghalangi/mengharamkankegiatan memikirkan kegiatannya.
Dekonstruksi cukup sopan santun dalam bekerja. Diamemulai kerjanya diarah pinggiran (margin) sebuah teks/karyauntuk selanjutnya melakukan eksposisi (memamerkan) danmenyingkapkan tabir pembungkus (dismantle) sehingga terkuakdan terlihatlah segenap oposisi dan kerawanan dari anggapan-anggapan yang dipakai untuk menstrukturkan teks/karya itu.
Setelah terkuak dan tersingkap, dekonstruksi lalu masukgelanggang mengambil alih posisi sebagai sebuah sistem.Bagaimana dia mengambil posisinya? Dengan menggelar apa yangoleh sejarah (dari disiplin pengetahuan yang ditangani) telahdisembunyikan atau disingkiran agar disiplin tadi memperolehidentitasnya.
Maksud dari dekonstruksi dlam bertindak seperti ituadalah untuk menggeser dan mengambil alih posisi kategori-kategori filosofikal yang biner (berpasang-pasangan), misalnya
pasangan absen/hadir (absen/presence). Pasangan-pasangan bineryang hierarkies itu tidak dilihat sebagai persoalan dalamposisi yang terisolasi atau teriteral (pinggiran), tetapidalam posisi yang sistemik dan represif. Disitu Derrida lalumengatakan bahwa tujuan dari arsitektur adalah mengontrolkomunikasi dan transportasi sebagai sektor kemasyarakatan,termasuk ekonomi. Memang dekonstruksi adalah bagian darikritik post-modern yang tujuan akhirnya adalah mengakhiridominasi dari rencana-rencana arsitektur modern.
Lebih lengkap tentang pemahaman dan perspektif baruarsitekturnya Jacques Derrida :
Tidak ada yang mutlak dalam arsitektur (cara, gaya,konsep) Tidak ada tokoh atau figur dalam arsitektur.
Perkembangan arsitektur harus mengarah pada keragamanpandangan dan tata nilai. Disamping penglihatan, inderalain harus dimanfaatkan secara seimbang. Arsitektur tidakidentik dengan produk bangunan bisa berupa : ide, gambar,model, dan fisik bangunan dalam jangkauan aksentuasi yangberbeda.
Gagasan dekonstruksi Jacques Derrida (sastra danfilsafat) dikembangkan dalam arsitektur oleh PeterEisenman dan Bernard Tschumi sebagai teori dan praktekarsitektur yang berciri penyangkalan terhadapepistemologi arsitektur klasik dan modern dan prinsipperancangannya non klasik, dekomposisi, desentring,dislokasi dan diskontinuitas.
Post-modernisme juga ditandai oleh pendalaman danpemekaran paradigma- paradigma teoritik ataupun oleh kerangk-kerangka kerja ideologikal yang kesemuanya itu membentukkerangka (struktur/structure) dari debat-debat tematik daridan tentang Post-Modernisme. Paradigma-paradigma ini di importdi luar arsitektur. Paradigma- paradigma utama yang mampumembentuk teori-teori arsitektur pada masa post- modernisme,diantaranya adalah paradigma fenomenologi dan paradigmalinguistik.
7. PARADIGMA ENVIRONMENTALIS
Sudah sejak lama para teoritisi yang berpengaruh padaarsitektur menghadirkan pandangan dan konsep-konsep tentangpentingnya menghadirkan kondisi lingkungan yang sehat,nyaman sebagai tujuan didalam perencanaan arsitektur.Teori yang memiliki kepedulian terhadap alam ini berfluktuasidari yang simpatik, harmonik, berintegrasi sehinggamenempatkan alam sebagai potensi untuk diekploitasi.
Landasan teori ini muncul sebagai sikap terhadap tapak,tempat (place) landscape dan pembuatan arsitektur utamanyadalam hal tektonika. Kelompok ini menekankan pada pelestarianlingkungan hidup dari kehancuran dan pencemaran. Pelestarianalam (bukit, pantai, hutan, sungai, laut, udara dsb). Dankebersihan lingkungan binaan menjadi motto dalam karya-karyamereka. Hasil kemajuan teknologi yang merusak dan pencemaranlingkungan binaan ditolak oleh mereka. Dengan paradigmalingkungan ini para perancang mendasarkan konsepnya denganpelestarian lingkungan dan penggunaan potensi alam sebesar-besarnya untuk perencanaan lingkungan binaan.
Vitruvius secara eksplisit telah mengungkapkan hal ini dalambukunya „The Ten Book On Architecture‟ yang kemudianditegaskan kembali oleh LeCorbusier (1953) bahwa : “Thesymphony of climate has not been understood. The sun differs along the curvature of the meridian, its intensity varies onthe crust of the earth according to its incidence. In thisplay many conditions are created which await edaquatesolutions. It is at this point that an authentic regionalismhas its rightful palce”. Dalam “De Architectural” Vitruviusjuga menyatakan bahwa bentukan arsitektur bangunan ituhendaknya berbeda antara Mesir dan Spanyol, di Pontus danRoma. Setiap negara dan wilayah mempunyai sifat yang berbeda(Olgyay, 1976 : 8)
Frank Lloyd Wright pada awal abad ke-20 menyampaikan suatufalsafah bahwa, setiap pemecahan masalah arsitektur selaluberhubungan dengan alam atau lingkungan seperti iklim,topografi dan bahan bangunan. Falsafah ini diterapkan padakaryanya Kauffman House “Falling Water‟ di Amerika Serikatyang menunjukan keseimbangan yang dihasilkan antarabidang-bidang masif horizontal dengan karang dan air terjun.
Alvar Aalto (1924) berfalsafah bahwa arsitektur adalah perencanaanyang memperhatikan pada alam dan tidak tergantung pada bahan-bahan buatan pabrik. Karya Alvar Aalto yang menonjolsehubungan dengan falsafah ini adalah Gereja di Muramme.
Di Amerika Latin Oscar Niemeyer (1937) menyatakan bahwaperencanaan arsitektur dipengaruhi oleh penyesuaian terhadapalam dan lingkungan, penguasaan secara fungsional kematangandan ketepatan dalam pengolahan serta pemilihan bentukbahan dan struktur. Salah satu karyanya yang berhasil didalammengolah sintesa arsitektur yang sadar lingkungan adalahGedung Kemetrian Pendidikan dan Kesehatan Rio De JaneiroBrazilia yang menampilkan dominasi bentuk yangmenggunakan peneduh cahaya (sunscreen).
Dalam perkembangan berikutnya pada era arsitektur modernmuncul teori-teori yang lebih spesifik mengenai pengaruh-pengaruh iklim, topografi dan bahan bangunan. Diantaranyaadalah Bernard Rudofsky (1964) yang menyatakan :
There is much to learn to architecture before itbecome an expert art the untutored builders in spaceand time demonstrated and admirable talent for fittingtheir building into the natural surrounding instead attrying to conquer the nature as we do they welcomethe vagiries of climate and challenger oftopography”.
Pada era selanjutnya yaitu era Post-Modern teori tentangbehaviourism berkembang menjadi sangat kompleks karenaarsitektur sebagai lingkungan binaan mengekspresikan berbagai
fungsi. Teori ini diantaranya dikembangkan oleh ChristianNorberg-Schulz dalam Intentions In Architecture (1987) bahwaarsitektur atau lingkungan binaan memiliki berbagai fungsidiantaranya adalah sebagai pengendali faktor alam (physicalcontrol), tempat kegiatan manusia (functional frame),lingkungan sosial (functional millieu) dan lingkungan simbol(symbol millieu).
Geoffrey Broadbent dalam Design In Architecture (1968)menyatakan : Arsitektur memancarkan/mengekspresikan berbagaifungsi yaitu filter lingkungan (environment filter), wadahkegiatan (container of activities), investasi (capitalInvestment), fungsi simbolik (symbolic function), pengubahperilaku (behaviour modifier) dan fungsi estetika(aesthetic function).
Salah satu contoh karya arsitektur yang berfungsi sebagaienvironment filter adalah Roof House di Selangor Kuala Lumpur(1984) dan Menara Mesiniaga karya Kenneth Yeang, dimana kulitbangunan didisain sebagai filter lingkungan. Demikian jugadengan Paul Rudolf di Jakarta dengan Wisma Dharmala-nyaberusaha mengakomodasi lingkungan kota dan iklim tropisJakarta untuk bangunan tinggi.
Tinjauan terhadap Arsitektur Tradisonal, dalamperkembangan peradabannya manusia sudah lama menemukan carauntuk menanggulangi pengaruh alam terhadap bangunan serta caramemanfaatkan potensi alam untuk menciptakan kondisi ruanghunian yang mereka inginkan. Tanpa energi mekanikdisain arsitektur tradisional adalah sangat genius,sederhana dan efisien.
Hal ini disinggung oleh LeCorbusier (1913) : “Despitemeager resource, primitive people have designed dwelling thatsuccesfully meet the severest climate problems, this simpleshelters often outperforms of present day architecture”.
Arg, Isaac, Pendekatan Kepada Perancangan Arsitektur, InterMatra.
Bakker, Anton, 1999, Kosmologi & Ekologi, Filsafat tentangKosmos sebagai Rumah
Tangga, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
Budihardjo, Eko, 1997, Arsitektur sebagai Warisan Budaya,Djambatan, Jakarta.
D.K. Ching F., 1993, Arsitektur, Bentuk, Ruang danSusunannya, terjemahan
Airlangga, Jakarta.
Hanoto, Paulus, Adjie, 1996, Arsitektur: Bentuk, Ruang danSusunannya, Erlangga, Surabaya.
Nesbitt, Kate, 1996, Theorizing a New Agenda For Architecture,Princeton Architectural
Press, New York.
Mangunwijaya, YB., 1988, Wastu Citra, Gramedia, Jakarta.
Olgyay, V., 1957, Design With Climate, Princeton UniversityPress, Princeton, NY. Roesmanto, Totok, 1999, Teori Arsitekturdi Dunia Timur, Bahan Penataran Dosen PTS angkatan III diBogor, tidak dipublikasikan.
Van, ornelis, de Ven, 1991, Ruang Dalam Arsitektur,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.