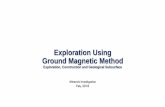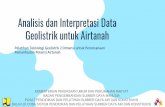laporan survei kepuasan masyarakat kementerian pertahanan ...
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya validasi dan
penyempurnaan Modul Desain Survei Geolistrik untuk Airtanah sebagai Materi Substansi
dalam Pelatihan Teknologi Geolistrik 2 Dimensi untuk Perencanaan Pemanfaatan Potensi
Airtanah. Modul ini disusun untuk memenuhi kebutuhan kompetensi dasar Aparatur Sipil
Negara (ASN) di bidang Sumber Daya Air.
Modul Desain Survei Geolistrik untuk Airtanah disusun dalam 7 (tujuh) bab yang terbagi atas
Pendahuluan, Materi Pokok, dan Penutup. Penyusunan modul yang sistematis diharapkan
mampu mempermudah peserta pelatihan dalam memahami desain survei geolistrik untuk
airtanah. Penekanan orientasi pembelajaran pada modul ini lebih menonjolkan partisipasi aktif
dari para peserta.
Akhirnya, ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Tim Penyusun dan
Narasumber Validasi, sehingga modul ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyempurnaan
maupun perubahan modul di masa mendatang senantiasa terbuka dan dimungkinkan
mengingat akan perkembangan situasi, kebijakan dan peraturan yang terus menerus terjadi.
Semoga Modul ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kompetensi ASN di bidang
Sumber Daya Air.
Bandung, Oktober 2019
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Sumber Daya Air dan Konstruksi
Ir. Herman Suroyo, MT
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
ii PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................................. i
DAFTAR ISI ........................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ................................................................................................................... v
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................. vi
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL ................................................................................ vii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ........................................................................................................... 1
1.2 Deskripsi singkat ........................................................................................................ 1
1.3 Tujuan Pembelajaran ................................................................................................. 1
1.3.1 Hasil Belajar ................................................................................................. 1
1.3.2 Indikator Hasil Belajar .................................................................................. 1
1.4 Materi Pokok dan Sub Materi Pokok ......................................................................... 2
BAB II KONFIGURASI SCHLUMBERGER .......................................................................... 5
2.1 Definisi Konfigurasi Schlumberger ............................................................................. 5
2.2 Peralatan dan Persyaratan ........................................................................................ 6
2.3 Prosedur Pengukuran ................................................................................................ 8
2.4 Perhitungan ................................................................................................................ 9
2.5 Pemodelan dan Interpretasi ..................................................................................... 10
2.6 Laporan .................................................................................................................... 11
2.7 Latihan ...................................................................................................................... 12
2.8 Rangkuman .............................................................................................................. 12
2.9 Evaluasi .................................................................................................................... 12
BAB III KONFIGURASI WENNER ...................................................................................... 15
3.1 Definisi Konfigurasi Wenner ..................................................................................... 15
3.2 Peralatan dan Persyaratan ...................................................................................... 17
3.3 Prosedur Pengukuran .............................................................................................. 18
3.4 Perhitungan .............................................................................................................. 19
3.5 Pemodelan dan Interpretasi ..................................................................................... 20
3.6 Laporan .................................................................................................................... 21
3.7 Latihan ...................................................................................................................... 21
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI iii
3.8 Rangkuman .............................................................................................................. 22
3.9 Evaluasi.................................................................................................................... 22
BAB IV KONFIGURASI POLE DIPOLE ............................................................................ 25
4.1 Definisi Pole Dipole .................................................................................................. 25
4.2 Peralatan dan Persyaratan ...................................................................................... 26
4.3 Prosedur Pengukuran .............................................................................................. 28
4.4 Perhitungan .............................................................................................................. 29
4.5 Pemodelan dan Interpretasi .................................................................................... 30
4.6 Laporan .................................................................................................................... 30
4.7 Latihan ..................................................................................................................... 31
4.8 Rangkuman .............................................................................................................. 31
4.9 Evaluasi.................................................................................................................... 31
BAB V PERALATAN SURVEI ........................................................................................... 33
5.1 Jenis – Jenis Alat Survei ......................................................................................... 33
5.2 Kelebihan (Manfaat) Alat Survei .............................................................................. 44
5.3 Kelemahan Alat Survei ............................................................................................ 46
5.4 Hambatan dan Penggunaan Alat Survei ................................................................. 47
5.5 Kalibrasi Alat Survei ................................................................................................. 50
5.6 Latihan ..................................................................................................................... 53
5.7 Rangkuman .............................................................................................................. 53
5.8 Evaluasi.................................................................................................................... 54
BAB VI PENENTUAN DESAIN SURVEI GEOLISTRIK .................................................... 55
6.1 Penentuan Konfigurasi Geolistrik ............................................................................ 55
6.1.1 Kawasan Karst........................................................................................... 56
6.1.2 Kawasan Pantai ......................................................................................... 56
6.1.3 Kawasan Pegunungan .............................................................................. 57
6.2 Prosedur Pengambilan Data ................................................................................... 57
6.2.1 Peralatan Lapangan ................................................................................... 57
6.2.2 Prosedur Pemindahan Konfigurasi Elektrode ........................................... 57
6.3 Latihan ..................................................................................................................... 59
6.4 Rangkuman .............................................................................................................. 59
6.5 Evaluasi.................................................................................................................... 60
BAB VII PENUTUP ............................................................................................................. 61
7.1 Simpulan .................................................................................................................. 61
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
iv PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
7.2 Tindak Lanjut ............................................................................................................ 61
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................ 63
GLOSARIUM ....................................................................................................................... 64
KUNCI JAWABAN .............................................................................................................. 65
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Nilai Tahanan Pendugaan untuk Tanah, Air dan Batuan (SNI 2818:2012) ........... 11
Tabel 3.1. Nilai Tahanan Pendugaan untuk Tanah, Air dan Batuan (SNI 2528: 2012) .......... 21
Tabel 5.1. Spesifikasi AGI Mini Sting R1 (agusia.com) ........................................................... 33
Tabel 5.2. Spesifikasi AGI Super Sting R8 (agusia.com) ........................................................ 35
Tabel 5.3. Spesifikasi ABEM SAS 1000/4000 (geoelectric.ru) ................................................ 37
Tabel 5.4. Spesifikasi OYO Mc Ohm Mark 2 (oyo.co.jp) ......................................................... 39
Tabel 5.5 Spesifikasi Resistivity Meter Nainura NRD 300 HF (alatukurteknik.com) .............. 40
Tabel 5.6. Spesifikasi G-Sound (geocis.com) .......................................................................... 41
Tabel 5.7. Spesifikasi IRES T300F (gfinstruments.cz) ............................................................ 42
Tabel 5.8. Spesifikasi ARES GF INSTRUMNET (geoelectric.ru) ............................................ 43
Tabel 5.9. Data Hasil Pengukuran Lapangan (Racka, 2014) .................................................. 49
Tabel 5.10. Harga Nilai Hambatan (ohm) (Dzikru, 2015) ........................................................ 51
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
vi PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Konfigurasi Elektrode Schlumberger (Maemuna, 2017) ...................................... 6
Gambar 3.1. Konfigurasi Elektrode Wenner (Murti, 2009) ...................................................... 16
Gambar 4.1. Konfigurasi Elektrode Pole Dipole (Andriyani, 2010) ......................................... 25
Gambar 4.2. Penempatan Awal Elektrode Arus dan Potensial pada Konfigurasi Pole Dipole
(Andriyani, 2010) ................................................................................................... 26
Gambar 5.1. AGI Mini Sting R1 (agusia.com) ......................................................................... 33
Gambar 5.2. AGI Super Sting R8 (agusia.com) ...................................................................... 35
Gambar 5.3. ABEM SAS 1000/4000 (geoelectric.ru) .............................................................. 37
Gambar 5.4. OYO Mc Ohm Mark 2 (oyo.co.jp) ....................................................................... 39
Gambar 5.5. Resistivity Meter Nainura NRD 300 HF (alatukurteknik.com) ........................... 40
Gambar 5.6. G-Sound (geocis.com) ........................................................................................ 41
Gambar 5.7. IRES T300F (gfinstruments.cz) .......................................................................... 42
Gambar 5.8. ARES GF INSTRUMENT (geoelectric.ru) .......................................................... 43
Gambar 5.9. Tampilan Panel Resistivitimeter Nainura NRD 22S (Racka, 2014)................... 48
Gambar 5.10. Instrumen Resistivitymeter Nainura Model NRD 22 (Dzikru, 2015) ................ 51
Gambar 5.11. Instrumentasi Alat yang Digunakan (Dzikru, 2015) ......................................... 52
Gambar 6.1. Penempatan Awal Elektrode Arus dan Potensial pada Konfigurasi Pole dipole
(Andriyani, 2010) ................................................................................................... 56
Gambar 6.2. Susunan Elektrode Konfigurasi Schlumberger (Racka, 2014) .......................... 58
Gambar 6.3. Susunan Elektrode Konfigurasi Wenner (Racka, 2014) .................................... 58
Gambar 6.4. Pengubahan Susunan Elektrode Konfigurasi Wenner (Racka, 2014) .............. 59
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI vii
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL
Deskripsi
Modul Desain Survei Geolistrik untuk Airtanah ini terdiri dari lima kegiatan belajar
mengajar. Kegiatan belajar pertama membahas Konfigurasi Schlumberger. Kegiatan
belajar kedua membahas Konfigurasi Wenner. Kegiatan belajar ketiga membahas
Konfigurasi Pole Dipole. Kegiatan belajar keempat membahas Peralatan Survei. Kegiatan
belajar kelima membahas Penentuan Desain Survei Geolistrik.
Peserta pelatihan mempelajari keseluruhan modul ini dengan cara yang berurutan.
Pemahaman setiap materi pada Pelatihan ini diperlukan untuk mampu memahami desain
survei geolistrik untuk airtanah.
Persyaratan
Dalam mempelajari modul pembelajaran ini, peserta pelatihan diharapkan dapat
menyimak dengan seksama penjelasan dari pengajar sehingga dapat memahami dengan
baik. Untuk menambah wawasan, peserta diharapkan dapat membaca terlebih dahulu
eksplorasi geofisika untuk airtanah.
Metode
Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, metode yang dipergunakan adalah dengan
kegiatan pemaparan yang dilakukan oleh Widyaiswara/ Fasilitator, adanya kesempatan
tanya jawab, dan diskusi.
Alat Bantu/ Media
Untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran ini, diperlukan Alat Bantu/ Media
pembelajaran tertentu, yaitu: LCD/ projector, Laptop, White board dengan spidol dan
penghapusnya, bahan tayang, modul dan/ atau bahan ajar.
Tujuan Kurikuler Khusus
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam mata pelatihan ini, Peserta mampu
memahami desain survey geolistrik untuk airtanah.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
viii PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pengembangan Air Tanah untuk Irigasi telah cukup lama di laksanakan di Indonesia,
yaitu diawali di Jawa Timur pada tahun 70 an dan saat ini telah berkembang hampir
diseluruh Indonesia meliputi seluruh Jawa dan terutama dikembangkan di Indonesia
Bagian Timur dari Bali sampai Papua dan sebagian di Wilayah Pulau Sumatera.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta di bidang Geolistrik
untuk Perencanaan Airtanah. Kompetensi yang dicapai oleh para peserta pelatihan
diharapkan dapat memahami desain survei geolistrik untuk airtanah. Untuk dapat
tercapainya maksud tersebut, maka dalam kegiatan pelatihan ini diperlukan mata
pelatihan Desain Survei Geolistrik untuk Airtanah.
1.2 Deskripsi singkat
Mata pelatihan ini membahas materi mengenai Konfigurasi Schlumberger;
Konfigurasi Wenner; Konfigurasi Pole Dipole; Peralatan Survei; serta Penentuan
Desain Survei Geolistrik. Pembelajaran ini disampaikan menggunakan metode
ceramah, tanya jawab dan diskusi.
1.3 Tujuan Pembelajaran
1.3.1 Hasil Belajar
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam mata pelatihan ini, Peserta mampu
memahami desain survey geolistrik untuk airtanah.
1.3.2 Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan:
a. Konfigurasi Schlumberger;
b. Konfigurasi Wenner;
c. Konfigurasi Pole Dipole;
d. Peralatan Survei;
e. Penentuan Desain Survei Geolistrik.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
2 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
1.4 Materi Pokok dan Sub Materi Pokok
Dalam modul desain survei geolistrik untuk airtanah ini akan membahas materi:
a) Konfigurasi Schlumberger
1) Definisi Konfigurasi Schlumberger
2) Peralatan dan Persyaratan
3) Prosedur Pengukuran
4) Perhitungan
5) Pemodelan dan Interpretasi
6) Laporan
7) Latihan
8) Rangkuman
9) Evaluasi
b) Konfigurasi Wenner
1) Definisi Konfigurasi Wenner
2) Peralatan dan Persyaratan
3) Prosedur Pengukuran
4) Perhitungan
5) Pemodelan dan Interpretasi
6) Laporan
7) Latihan
8) Rangkuman
9) Evaluasi
c) Konfigurasi Pole Dipole
1) Definisi Pole Dipole
2) Peralatan dan Persyaratan
3) Prosedur Pengukuran
4) Perhitungan
5) Pemodelan dan Interpretasi
6) Laporan
7) Latihan
8) Rangkuman
9) Evaluasi
d) Peralatan Survei
1) Jenis – Jenis Alat Survei
2) Kelebihan (Manfaat) Alat Survei
3) Kelemahan Alat Survei
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 3
4) Hambatan dan Penggunaan Alat Survei
5) Kalibrasi Alat Survei
6) Latihan
7) Rangkuman
8) Evaluasi
e) Penentuan Desain Survei Geolistrik
1) Penentuan Konfigurasi Geolistrik
2) Prosedur Pengambilan Data
3) Latihan
4) Rangkuman
5) Evaluasi
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
4 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 5
BAB II
KONFIGURASI SCHLUMBERGER
2.1 Definisi Konfigurasi Schlumberger
Konfigurasi Schlumberger merupakan teknik sounding, jarak antar arus dan
elektrode bervariasi, sehingga yang di pindah-pindahkan hanya bentangan arus.
Konfigurasi ini paling sering digunakan untuk mencari sumber air. Idealnya jarak MN
(potensial) dibuat sekecil – kecilnya, sehingga jarak MN secara teoritis tidak
berubah, dikarenakan keterbatasan kepekaan alat ukur, maka ketika jarak AB (arus)
sudah relatif besar maka jarak MN hendaknya diubah.
Perubahan jarak MN hendaknya tidak lebih besar seperlima jarak AB.
Kelebihan konfigurasi Schlumberger sebagai berikut :
a) Mampu mendeteksi adanya non-homogenitas lapisan batuan pada permukaan
(membandingkan nilai resistivitas semu ketika terjadi perubahan jarak elektrode
MN/2).
b) Mudah untuk digunakan untuk pemula (pemindahan elektrode relatif lebih
praktis).
Kelemahan konfigurasi Schlumberger sebagai berikut :
a) Pembacaan tegangan pada elektrode MN lebih kecil ketika jarak AB yang relatif
jauh, sehingga diperlukan multimeter yang mempunyai karakteristik ‘high
impedance’ dengan akurasi tinggi (men display tegangan minimal 4 digit atau 2
digit di belakang koma).
b) Memerlukan peralatan pengirim arus yang mempunyai tegangan listrik DC yang
sangat tinggi untuk mengatasi pembacaan tegangan MN yang kecil.
Indikator Hasil Belajar:
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan konfigurasi schlumberger.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
6 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
Gambar 2.1. Konfigurasi Elektrode Schlumberger (Maemuna, 2017)
2.2 Peralatan dan Persyaratan
Peralatan dan persyaratan yang digunakan dalam konfigurasi Schlumberger adalah
sebagai berikut:
a) Peralatan
Jenis peralatan yang digunakan harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku
dan meliputi:
1) Satu buah pengirim arus searah atau bolak-balik, jika arus bolak-balik
dengan frekuensi maksimum 30 Hz. Sumber arus disesuaikan dengan
kebutuhan, dan ketelitian pembacaan alat minimal 1 mA dengan sumber
arus yang cukup. Pengukuran dengan sumber arus searah sebaiknya
elektrode yang tidak berpolarisasi untuk elektrode potensial.
2) Satu buah pengukur tegangan dengan ketelitian pembacaan 0,001 mV
atau alat yang terukur tahanan listriknya dengan ketelitian pembacaan 0,01
mΩ.
3) Kompas geologi.
4) Global Position System (GPS) untuk menentukan lokasi titik pengukuran.
5) Pengukur ketinggian muka tanah, seperti altimeter, alat penyipat datar dan
alat penyipat ruang.
6) Empat buah gulungan kabel jenisnya disesuaikan dengan alat geolistrik
tahanan jenis dan panjangnya sesuai kebutuhan.
7) Lima buah elektrode yang disesuaikan dengan peralatan.
8) Empat buah palu besi untuk menancapkan elektrode kedalam tanah.
9) Dua gulung tali ukur dengan panjang minimum 300 m dan roll meter.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 7
10) Semua alat ukur harus dikalibrasi, sesuai dengan ketentuan spesifikasinya.
11) Tiga buah alat komunikasi atau yang sejenis untuk operator dan pemegang
elektrode arus.
12) Peralatan reparasi (tool kit).
b) Persyaratan pengukuran
1) Mempelajari keadaan geologi dan geohidrologi di sekitar daerah
pengukuran.
2) Perlapisan di bawah permukaan mempunyai kemiringan maksimum 30°.
3) Pemasangan elektrode harus mempunyai kontak yang baik dengan tanah.
4) Pemasangan elektrode diusahakan dalam satu garis lurus.
5) Jarak elektrode potensial harus berada 0,2 kali jarak elektrode arus
(MN=1/5 AB)
6) Perpindahan elektrode potensial minimum 3 pasangan titik pengukuran
yang saling tumpang tindih
7) Pengukuran dilakukan pada daerah yang relatif datar dan pada waktu tidak
hujan
8) Jumlah titik pengukuran tersebar merata dengan cara grid
9) Arah bentangan pengukuran harus sejajar dengan arah perlapisan batu
atau tanah.
10) Pengukuran di sekitar sungai atau pantai, arah bentangan harus sejajar
pantai atau sungai.
11) Arah bentangan pengukuran harus diusahakan pada lokasi yang tidak
terpengaruh oleh benda-benda yang dapat mempengaruhi ketelitian
pengukuran (seperti rel kereta api, saluran pipa, saluran kawat listrik).
12) Apabila persyaratan pada huruf k) tidak bisa dipenuhi, maka arah
bentangan harus memotong tegak lurus benda yang mempengaruhi
tersebut.
13) Bila ada sumur bor yang berdekatan dengan lokasi pengukuran, tentukan
lokasi sumur bor di peta, catat log bornya dan lakukan pengukuran pada
lokasi sumur bor untuk pembanding.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
8 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
2.3 Prosedur Pengukuran
Prosedur pengukuran dalam konfigurasi Schlumberger memiliki tahapan sebagai
berikut:
a) Tentukan titik pengukuran.
b) Gambar titik pengukuran di peta.
c) Tentukan arah bentangan pengukuran.
d) Isilah tabel pengukuran meliputi:
1) Nomor titik pengukuran;
2) Lokasi pengukuran (kampung, desa);
3) Elevasi muka tanah;
4) Tanggal, bulan dan tahun pengukuran;
5) Nama operator;
6) Nama pengawas;
7) Nama penanggung jawab.
e) Pasang elektrode potensial (MN/2) pada jarak yang terpendek minimal 0,5 m
dan pasang elektrode arus (AB/2) pada jarak 1,5 m (Gambar 2.1).
f) Hubungkan elektrode A dan B ke alat pengirim arus.
g) Hubungkan elektrode M dan N ke pengukur potensial pada alat geolistrik.
h) Catat besar arus yang dikirim dalam ampere.
i) Catat besar tegangan dalam volt atau besar tahanan listrik dalam ohm.
j) Pindahkan elektrode arus (AB/2) pada jarak 2m.
k) Ulangi kegiatan serupa dari e) sampai j) untuk jarak elektrode berikutnya (Tabel
2.1).
l) Bila ada sumur bor yang berdekatan dengan lokasi pengukuran, gambarkan
lokasi sumur bor pada peta dan catat bor lognya.
Parameter yang di ukur :
a) Jarak antara stasiun dengan elektrode-elektrode (AB/2 dan MN/2)
b) Arus (I)
c) Beda Potensial (∆ V)
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 9
2.4 Perhitungan
Perhitungan tahanan jenis dengan menggunakan rumus-rumus berikut:
Tahanan jenis semu:
ρa = K ∆V
I……………………………………………………………… (1.1)
K = π (AB/2)2−(MN/2)2
MN…………………………….……….…………(1.2)
Keterangan :
ρa adalah tahanan jenis semu (Ωm)
K adalah faktor koreksi geometris (m)
Δ V adalah beda potensial (V)
I adalah arus listrik (A)
π adalah konstanta bernilai 3.142
AB adalah jarak antara elektode arus (m)
MN adalah jarak antara elektrode potensial
Parameter yang di hitung :
a) Tahanan jenis (R)
b) Faktor geometrik (K)
c) Tahanan jenis semu (ρ)
Contoh Soal:
Berapakah nilai faktor koreksi geometris jika diketahui jarak antar elektroda arus 1,5
m, jarak antara elektroda potensial 0,25 m?
Jawab :
Diketahui :
AB = 1,5 m
MN = 0,25 m
Ditanyakan: K?
Jawab:
K = 3,142 (1,5/2)2−(0,25/2)2
0,25
K = 7,85
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
10 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
2.5 Pemodelan dan Interpretasi
Pemodelan dan interpretasi dengan menganalisis data hasil pengukuran dengan
tahapan sebagai berikut:
a) Lakukan pemodelan menurut ketentuan yang berlaku
1) Pemodelan tidak langsung adalah penyesuaian lengkung lapangan
dengan lengkung baku sesuai data yang didapat. Penyesuaian lengkung
tersebut menggunakan legkung baku dan lengkung bantu.
2) Pemodelan langsung adalah pemodelan menggunakan software
Res2Dinv.
3) Tentukan nilai dan ketebalannya untuk setiap lapisan.
b) Lakukan pendugaan air tanah dengan menganalisis data hasil pemodelan dan
interpretasi untuk mendapatkan keadaan geologi bawah permukaan dan
kondisi air tanahnya, dengan tahapan sebagai berikut:
1) Urutan lapisan batuan secara tegak dari lengkung setiap titik pengukuran
2) Tentukan jenis litologi batuan berdasarkan tahanan jenisnya sesuai
dengan tabel 1.1
3) Tentukan batas lapisan batuan secara tegak dan bila ada dengan bor log
sumur di sekitar titik pengukuran
4) Korelasikan hasil pendugaan setiap titik pengukuran dengan titik-titik
pengukuran lainnya, dan dengan bor log sumur yang di sekitar lokasi
pengukuran untuk dibuat penampang geologi bawah permukaan
5) Lakukan interpretasi kedudukan lapisan yang mengandung air tanah atau
akuifer berdasarkan nilai tahanan jenisnya
6) Perhatikan kondisi geohidrologi di daerah pengukuran dalam interpretasi
akuifer
7) Tentukan lapisan batuan yang mengandung air tanah atau akuifer
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 11
Tabel 2.1. Nilai Tahanan Pendugaan untuk Tanah, Air dan Batuan (SNI 2818:2012)
Tahanan Tanah ƿ (ohm meter)
daerah basah 50 sampai 200
daerah kering 100 sampai 500
200 sampai 1000 (terkadang di bawah 50 jika tanah
mengandung garam)
Air ƿ (ohm meter)
air tanah 1 sampai 100
air hujan 30 sampai 1000
air laut di bawah 0,2
es 105 sampai 108
Tipe batuan ƿ (ohm meter)
batuan beku dan
metamorfis 100 sampai 10000
sedimen terkonsolidasi 10 sampai 100
sedimen tak
terkonsolidasi 1 1 sampai 100
2.6 Laporan
Laporan pengukuran dibuat dalam satu buku yang berisi data yang diperlukan,
meliputi:
a) Keadaan geologi permukaan di daerah penyelidikan, bila ada
b) Penampang geologi berdasarkan harga tahanan jenis dari hasil interpretasi
dalam bentuk simbol yang meliputi:
1) Satuan lapisan batuan dengan batas vertikal dan lateral
2) Struktur geologi
c) Kondisi air tanah hasil analisis dari sifat keairan nya batu atau tanah terhadap
geologi permukaan
d) Penentuan untuk lokasi titik pengeboran uji yang sangat diperlukan oleh
pemakai data
e) Laporan ini ditandatangani oleh petugas dari instansi yang berwenang
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
12 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
2.7 Latihan
1. Sebutkan prosedur pengisian tabel pengukuran!
2. Sebutkan kelemahan konfigurasi Schlumberger!
3. Sebutkan parameter yang diukur dan dihitung dalam konfigurasi Schlumberger!
2.8 Rangkuman
Tata cara pengukuran geolistrik Schlumberger untuk eksplorasi air tanah digunakan
sebagai acuan dan pegangan dalam menentukan jenis batu atau tanah, batas
lapisan, ketebalan dan menduga akuifer berdasarkan tahanan jenisnya.
Pemodelan dan interpretasi langsung menggunakan software sedangkan untuk
pemodelan dan interpretasi tidak langsung adalah dengan penyesuaian lengkung
lapangan dan lengkung baku.
Ada lima tahapan dalam survei geolistrik konfigurasi Schlumberger yaitu peralatan
survei, persyaratan survei, prosedur pengukuran survei, perhitungan, pemodelan,
interpretasi, dan laporan.
2.9 Evaluasi
1. Jarak penempatan elektroda potensial pada konfigurasi Schlumberger
adalah.....
a. Jarak MN (potensial) dibuat sekecil-kecilnya, sehingga jarak MN secara
teoritis tidak berubah, dikarenakan keterbatasan kepekaan alat ukur, maka
ketika jarak AB (arus) sudah relatif besar maka jarak MN hendaknya
diubah. Perubahan jarak MN hendaknya tidak lebih besar seperlima jarak
AB.
b. Jarak AB (arus) dibuat sekecil-kecilnya, sehingga jarak AB secara teoritis
tidak berubah, dikarenakan keterbatasan kepekaan alat ukur, maka ketika
jarak MN (potensial) sudah relatif besar maka jarak AB hendaknya diubah.
Perubahan jarak AB hendaknya tidak lebih besar seperlima jarak MN.
c. Jarak MN (potensial) dibuat sama dengan jarak AB, sehingga jarak MN dan
AB secara teoritis tidak berubah, dikarenakan keterbatasan kepekaan alat
ukur, maka ketika jarak AB (arus) sudah relatif besar maka jarak MN
hendaknya diubah. Perubahan jarak MN hendaknya tidak lebih besar
seperlima jarak AB.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 13
d. Jarak AB (arus) dibuat tidak sama, sehingga jarak AB secara teoritis
berubah, dikarenakan keterbatasan kepekaan alat ukur, maka ketika jarak
MN (potensial) sudah relatif besar maka jarak AB hendaknya diubah.
Perubahan jarak AB hendaknya tidak lebih besar sepertiga jarak MN.
2. Kelebihan Konfigurasi Schlumber adalah…..
a. Pembacaan tegangan pada elektrode MN lebih kecil ketika jarak AB yang
relatif jauh, sehingga diperlukan multimeter yang mempunyai karakteristik
‘high impedance’ dengan akurasi tinggi (men display tegangan minimal 4
digit atau 2 digit di belakang koma).
b. Mampu mendeteksi adanya non-homogenitas lapisan batuan pada
permukaan (membandingkan nilai resistivitas semu ketika terjadi
perubahan jarak elektrode MN/2).
c. Memerlukan peralatan pengirim arus yang mempunyai tegangan listrik DC
yang sangat tinggi untuk mengatasi pembacaan tegangan MN yang kecil.
d. Tidak mudah untuk digunakan untuk pemula (pemindahan elektrode relatif
lebih rumit).
3. Berikut ini Parameter yang tidak diukur konfigurasi schlumberger adalah…..
a. Jarak antara stasiun dengan elektrode-elektrode (AB/2 dan MN/2)
b. Arus (I)
c. Gaya
d. Beda Potensial (∆ V)
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
14 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 15
BAB III
KONFIGURASI WENNER
3.1 Definisi Konfigurasi Wenner
Konfigurasi ini digunakan untuk mendapat profil dari permukaan lapangan, yang
biasa disebut dengan teknik mapping. Jarak antar arus dan elektrode sama.
Sehingga ketika ingin dipindahkan, semua dipindahkan. konfigurasi ini paling sering
digunakan untuk mencari bahan tambang.
Kelebihan konfigurasi Wenner adalah sebagai berikut:
a) Memiliki sinyal yang kuat. Hal ini dapat menjadi faktor penting jika survei
dilakukan di daerah dengan noise yang tinggi.
b) Ketelitian pembacaan tegangan pada elektrode MN (potensial) lebih baik meski
jarak relatif besar karena elektrode MN relatif lebih dekat dengan elektrode AB
(arus). Sehingga dapat menggunakan multimeter dengan impedansi yang
relatif lebih kecil.
Kekurangan konfigurasi Wenner adalah sebagai berikut:
a) Cakupan horizontal relatif buruk seiring meningkatnya jarak elektrode.
Akibatnya, pada konfigurasi ini tidak bisa mendeteksi homogenitas batuan di
dekat permukaan yang bisa berpengaruh terhadap hasil perhitungan.
b) Data yang didapat dari cara konfigurasi Wenner sangat sulit untuk
menghilangkan faktor non homogenitas batuan, sehingga hasil perhitungan
menjadi kurang akurat.
c) Memiliki kedalaman yang cukup sedang.
d) Kekuatan sinyal berbanding terbalik dengan faktor geometris yang digunakan
untuk menghitung nilai resistivitas
Indikator Hasil Belajar:
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan konfigurasi wenner.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
16 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
Jarak MN pada konfigurasi Wenner selalu sepertiga dari jarak AB. Bila jarak AB
diperbesar, maka jarak MN juga harus diubah sehingga jarak MN tetap sepertiga
jarak AB.
Gambar 3.1. Konfigurasi Elektrode Wenner (Murti, 2009)
Tata cara pengukuran geolistrik Wenner untuk eksplorasi air tanah digunakan
sebagai acuan dan pegangan dalam menentukan jenis batu atau tanah, batas
lapisan, ketebalan dan menduga akuifer berdasarkan tahanan jenisnya.
Pengukuran dilaksanakan dengan empat elektrode yang ditancapkan di permukaan
tanah dengan susunan elektrode Wenner dan jarak elektrode mencerminkan
kedalaman yang diukur. Sumber arus yang berupa arus searah (direct current) atau
arus bolak balik (alternating current) dikirim melalui dua buah elektrode arus dan
menghasilkan perbedaan potensial yang terekam oleh dua buah elektrode
potensial, sehingga dapat dihitung tahanan (resistance) batu atau tanah yang
terukur.
Perhitungan tahanan jenis semu (apparent resistivity) dilakukan dengan koreksi
geometri yang tergantung pada jarak dan susunan elektrode yang digunakan.
Penandaan antara kedalaman dengan tahanan jenis, sebagai bahan interpretasi
untuk menentukan jenis batu atau tanah, batas lapisan, ketebalan dan menduga
akuifer berdasarkan tahanan jenisnya.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 17
3.2 Peralatan dan Persyaratan
Peralatan dan persyaratan yang digunakan dalam konfigurasi Wenner adalah
sebagai berikut:
a) Peralatan
Jenis peralatan yang digunakan harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku
dan meliputi:
1) Satu buah pengirim arus searah atau bolak-balik, jika arus bolak-balik
dengan frekuensi maksimum 30 Hz. Sumber arus disesuaikan dengan
kebutuhan, dan ketelitian pembacaan alat minimal 1 mA dengan sumber
arus yang cukup. Pengukuran dengan sumber arus searah sebaiknya
elektrode yang tidak berpolarisasi untuk elektrode potensial.
2) Satu buah pengukur tegangan dengan ketelitian pembacaan 0,001 mV
atau alat yang terukur tahanan listriknya dengan ketelitian pembacaan 0,01
mΩ.
3) Kompas geologi.
4) Global Position System (GPS) untuk menentukan lokasi titik pengukuran.
5) Pengukur ketinggian muka tanah, seperti altimeter, alat penyipat datar dan
alat penyipat ruang.
6) Empat buah gulungan kabel jenisnya disesuaikan dengan alat geolistrik
tahanan jenis dan panjangnya sesuai kebutuhan.
7) Lima buah elektrode yang disesuaikan dengan peralatan.
8) Empat buah palu besi untuk menancapkan elektrode kedalam tanah.
9) Dua gulung tali ukur dengan panjang minimum 300 m dan roll meter.
10) Semua alat ukur harus dikalibrasi, sesuai dengan ketentuan spesifikasinya,
dan atau pada saat diperlukan.
11) Tiga buah alat komunikasi atau yang sejenis untuk operator dan pemegang
elektrode arus.
12) Peralatan reparasi (tool kit).
b) Persyaratan pengukuran
Pada saat pengukuran harus memperhatikan hal-hal berikut:
1) Mempelajari keadaan geologi dan geohidrologi di sekitar daerah
pengukuran.
2) Perlapisan di bawah permukaan mempunyai kemiringan maksimum 30°.
3) Pendugaan sampai kedalaman 200 m.
4) Pemasangan elektrode diusahakan dalam satu garis lurus.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
18 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
5) Perpindahan jarak elektrode selalu sama.
6) Pengukuran pada daerah yang relatif datar dan pada waktu tidak hujan.
7) Jumlah titik pengukuran merata dengan cara grid.
8) Arah bentangan pengukuran harus sejajar dengan arah perlapisan batu
atau tanah.
9) Pengukuran di sekitar sungai atau pantai, arah bentangan harus sejajar
pantai atau sungai.
10) Arah bentangan pengukuran harus diusahakan pada lokasi yang tidak
terpengaruh oleh benda-benda yang dapat mempengaruhi ketelitian
pengukuran (seperti rel kereta api, saluran pipa, saluran kawat listrik).
11) Apabila persyaratan pada huruf j) tidak bisa dipenuhi, maka arah
bentangan harus memotong tegak lurus benda yang mempengaruhi
tersebut.
12) Bila ada sumur bor yang berdekatan dengan lokasi pengukuran, tentukan
lokasi sumur bor di peta, catat log bornya dan lakukan pengukuran pada
lokasi sumur bor untuk pembanding.
3.3 Prosedur Pengukuran
Pengukuran dilakukan dengan tahapan:
a) Tentukan titik pengukuran.
b) Gambar titik pengukuran di peta.
c) Tentukan arah bentangan pengukuran.
d) Isilah tabel pengukuran meliputi:
1) Nomor titik pengukuran;
2) Lokasi pengukuran (kampung, desa);
3) Elevasi muka tanah;
4) Tanggal, bulan dan tahun pengukuran;
5) Nama operator;
6) Nama pengawas;
7) Nama penanggung jawab.
e) Pasang elektrode pada jarak yang terpendek dengan jarak elektrode harus
sama AM = MN = NB = 1 m (Gambar 3.1).
f) Hubungkan elektrode A dan B ke alat pengirim arus.
g) Hubungkan elektrode M dan N ke pengukur potensial pada alat geolistrik.
h) Catat besar arus yang dikirim dalam ampere.
i) Catat besar tegangan dalam volt atau besar tahanan listrik dalam ohm.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 19
j) Pindahkan elektrode dengan jarak 1,5 m.
k) Ulangi kegiatan serupa dari e) sampai j) untuk jarak elektrode berikutnya (Tabel
3.1).
l) Bila ada sumur bor yang berdekatan dengan lokasi pengukuran, gambarkan
lokasi sumur bor pada peta dan catat bor lognya.
3.4 Perhitungan
Perhitungan tahanan jenis dengan menggunakan rumus-rumus berikut:
Tahanan jenis semu:
𝛒𝐚 = 𝐊 ∆𝐕
𝐈…………………………………………………………(2.1)
𝐊 = 𝟐 𝛑 𝛂 ……………………….………………………………(2.2)
Keterangan:
ρa adalah tahanan jenis semu (Ωm)
K adalah faktor koreksi geometris (m)
Δ V adalah beda potensial (V)
I adalah arus listrik (A)
π adalah konstanta bernilai 3.142
a adalah jarak AB/3 atau jarak MN (m)
Contoh Soal:
Berapakah tahanan jenis semu jika diketahui beda potensial 1,5 A dan arus listrik
adalah 0,137 A dan faktor koreksi geometris adalah 5,89 ?
Jawab:
Diketahui :
Δ V = 1,5 m
I = 0,137 A
K = 5,89
Ditanyakan:
ρa?
Jawab:
ρa = 5,891,5
0,137
ρa = 64,48 Ωm
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
20 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
3.5 Pemodelan dan Interpretasi
Pemodelan dan interpretasi dengan menganalisis data hasil pengukuran dengan
tahapan sebagai berikut:
a) Lakukan pemodelan menurut ketentuan yang berlaku
1) Pemodelan tidak langsung adalah penyesuaian lengkung lapangan
dengan lengkung baku sesuai data yang didapat. penyesuaian lengkung
tersebut menggunakan legkung baku dan lengkung bantu.
2) Pemodelan langsung adalah pemodelan menggunakan software
Res2Dinv.
3) Tentukan nilai dan ketebalannya untuk setiap lapisan.
b) Lakukan pendugaan air tanah dengan menganalisis data hasil pemodelan dan
interpretasi untuk mendapatkan keadaan geologi bawah permukaan dan
kondisi air tanahnya, dengan tahapan sebagai berikut:
1) Urutan lapisan batuan secara tegak dari lengkung setiap titik pengukuran.
2) Tentukan jenis litologi batuan berdasarkan tahanan jenisnya sesuai
dengan tabel 3.1.
3) Tentukan batas lapisan batuan secara tegak dan bila ada dengan bor log
sumur di sekitar titik pengukuran.
4) Korelasikan hasil pendugaan setiap titik pengukuran dengan titik-titik
pengukuran lainnya, dan dengan bor log sumur yang di sekitar lokasi
pengukuran untuk dibuat penampang geologi bawah permukaan.
5) Lakukan interpretasi kedudukan lapisan yang mengandung air tanah atau
akuifer berdasarkan nilai tahanan jenisnya.
6) Perhatikan kondisi geohidrologi di daerah pengukuran dalam interpretasi
akuifer.
7) Tentukan lapisan batuan yang mengandung air tanah atau akuifer.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 21
Tabel 3.1. Nilai Tahanan Pendugaan untuk Tanah, Air dan Batuan (SNI 2528: 2012)
Tahanan Tanah ƿ (ohm meter)
- daerah basah 50 sampai 200
- daerah kering 100 sampai 500
- daerah sangat kering
mengandung garam
200 sampai 1000 (terkadang di bawah 50 jika tanah
mengandung garam)
Air ƿ (ohm meter)
- air tanah 1 sampai 100
- air hujan 30 sampai 1000
- air laut di bawah 0,2
- es 105 sampai 108
Tipe batuan ƿ (ohm meter)
- batuan beku dan metamorfis 100 sampai 10000
- sedimen terkonsolidasi 10 sampai 100
- sedimen tak terkonsolidasi 1 sampai 100
3.6 Laporan
Laporan pengukuran dibuat dalam satu buku yang berisi data yang diperlukan,
meliputi:
a) Keadaan geologi permukaan di daerah penyelidikan, bila ada.
b) Penampang geologi berdasarkan harga tahanan jenis dari hasil interpretasi
dalam bentuk simbol yang meliputi:
1) Satuan lapisan batuan dengan batas vertikal dan lateral
2) Struktur geologi
c) Kondisi air tanah hasil analisis dari sifat keairan nya batu atau tanah terhadap
geologi permukaan.
d) Penentuan untuk lokasi titik pengeboran uji yang sangat diperlukan oleh
pemakai data.
e) Laporan ini ditandatangani ole petugas dari instansi yang berwenang.
3.7 Latihan
1. Sebutkan tiga langkah awal prosedur pengukuran!
2. Sebutkan tiga perbedaan konfigurasi wenner dan konfigurasi schlumberger!
3. Sebutkan nilai tahan tanah untuk sedimen terkonsolidasi!
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
22 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
3.8 Rangkuman
Tata cara pengukuran geolistrik Wenner untuk eksplorasi air tanah digunakan
sebagai acuan dan pegangan dalam menentukan jenis batu atau tanah, batas
lapisan, ketebalan dan menduga akuifer berdasarkan tahanan jenisnya.
Pemodelan dan interpretasi langsung menggunakan software sedangkan untuk
pemodelan dan interpretasi tidak langsung adalah dengan penyesuaian lengkung
lapangan dan lengkung baku.
Ada lima tahapan dalam survei geolistrik metode Wenner yaitu peralatan,
persyaratan survei, prosedur pengukuran survei, perhitungan, pemodelan,
interpretasi, laporan.
3.9 Evaluasi
1. Keunggulan Konfigurasi Wenner adalah.....
a. Ketelitian pembacaan tegangan pada elektroda MN lebih baik dengan
angka yang relatif besar karena elektroda MN relatif dekat dengan
elektroda AB.
b. Pembacaan tegangan pada elektroda MN lebih kecil ketika jarak AB relatif
jauh.
c. Dapat mendeteksi homogenitas batuan di dekat permukaan yang
berpengaruh terhadap jawaban perhitungan.
d. Mampu mendeteksi adanya non homogenitas lapisan batuan pada
permukaan.
2. Tata cara pengukuran geolistrik Wenner untuk eksplorasi air tanah digunakan
sebagai acuan dan pegangan dalam menentukan, kecuali.....
a. Jenis batu atau tanah
b. Arus
c. Batas lapisan
d. Ketebalan
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 23
3. Nilai tahanan tanah daerah basah adalah….. ƿ (ohm meter)
a. 100 – 500
b. 200 – 1000
c. 50 – 200
d. 50 – 150
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
24 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 25
BAB IV
KONFIGURASI POLE DIPOLE
4.1 Definisi Pole Dipole
Pole-dipole merupakan salah satu konfigurasi yang dapat gunakan jika ingin
melakukan pendugaan atau investigasi geologi bawah permukaan yang kurang dari
500m dibawah permukaan tanah.
Konfigurasi pole-dipole memiliki penetrasi yang lebih dalam ± 65% dibandingkan
konfigurasi dipole-dipole, kelemahan dari konfigurasi pole-dipole adalah tingkat
akurasi dari posisi benda atau obyek yang kurang akurat dibandingkan konfigurasi
dipole-dipole, hal ini disebabkan oleh konfigurasi elektrode yang tidak simetris.
Konfigurasi pole dipole jarak antar arus dan antar elektrode berada dalam satu garis
dimana jarak antar elektrode arus tidak terbatas. Pada konfigurasi pole ipole
digunakan satu elektrode arus dan dua elektrode potensial. Untuk elektrode arus
C2 ditempatkan pada sekitar lokasi penelitian dengan jarak minimum 5 kali spasi
terpanjang C1-P1
Gambar 4.1. Konfigurasi Elektrode Pole Dipole (Andriyani, 2010)
Pada gambar 4.1 dimana C1 dan C2 adalah elektrode arus P1 dan P2 adalah
elektrode potensial, a adalah spasi elektrode, n adalah perbandingan jarak antara
elektrode C1 dan P1 atau banyaknya lapisan pengukuran dengan spasi “a”, ∞ adalah
jarak elektrode arus (C2) yang dipasang tidak terhingga. Faktor geometri adalah
besaran koreksi posisi kedua elektrode potensial terhadap letak kedua elektrode
arus.
Indikator Hasil Belajar:
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan konfigurasi pole dipole.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
26 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
Berdasarkan letak elektrode maka faktor geometri untuk konfigurasi pole dipole
adalah = 𝟐 𝛑 𝐧 (𝒏𝟐 + 𝐧) , dimana konfigurasi pole dipole ini menghitung arus yang
digunakan dari jarak tidak terhingga, sehingga tegangan yang diperoleh nilainya
bervariasi.
Gambar 4.2 merupakan ilustrasi penempatan awal elektrode untuk konfigurasi pole-
dipole dimana elektrode arus C2 terletak jauh diluar jalur rencana pengukuran.
Sebagai contoh, jika kita melakukan pengukuran resistivity dari titik 0 ke arah kanan
dari gambar ilustrasi dibawah ini sepanjang 1000 m, maka penempatan elektrode
arus C2 bisa diletakkan di sisi kiri dari titik 0 sejauh 1000 m pula ke arah kiri.
Gambar 4.2. Penempatan Awal Elektrode Arus dan Potensial pada Konfigurasi
Pole Dipole (Andriyani, 2010)
4.2 Peralatan dan Persyaratan
Peralatan dan persyaratan yang digunakan dalam konfigurasi Pole Dipole adalah
sebagai berikut:
a) Peralatan
Jenis peralatan yang digunakan harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku
dan meliputi:
1) Satu buah pengirim arus searah atau bolak-balik, jika arus bolak-balik
dengan frekuensi maksimum 30 Hz. Sumber arus disesuaikan dengan
kebutuhan, dan ketelitian pembacaan alat minimal 1 mA dengan sumber
arus yang cukup. Pengukuran dengan sumber arus searah sebaiknya
elektrode yang tidak berpolarisasi untuk elektrode potensial.
2) Satu buah pengukur tegangan dengan ketelitian pembacaan 0,001 mV
atau alat yang terukur tahanan listriknya dengan ketelitian pembacaan 0,01
mΩ.
3) Kompas geologi.
4) Global Position System (GPS) untuk menentukan lokasi titik pengukuran.
5) Pengukur ketinggian muka tanah, seperti altimeter, alat penyipat datar dan
alat penyipat ruang.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 27
6) Empat buah gulungan kabel jenisnya disesuaikan dengan alat geolistrik
tahanan jenis dan panjangnya sesuai kebutuhan.
7) Lima buah elektrode yang disesuaikan dengan peralatan.
8) Empat buah palu besi untuk menancapkan elektrode kedalam tanah.
9) Dua gulung tali ukur dengan panjang minimum 300 m dan roll meter.
10) Semua alat ukur harus dikalibrasi, sesuai dengan ketentuan spesifikasinya,
dan atau pada saat diperlukan.
11) Tiga buah alat komunikasi atau yang sejenis untuk operator dan pemegang
elektrode arus.
12) Peralatan reparasi (tool kit).
b) Persyaratan pengukuran
Pada saat pengukuran harus memperhatikan hal-hal berikut:
1) Mempelajari keadaan geologi dan geohidrologi di sekitar daerah
pengukuran
2) Perlapisan di bawah permukaan mempunyai kemiringan maksimum 30°
3) Pendugaan sampai kedalaman 200 m
4) Pemasangan elektrode diusahakan dalam satu garis lurus
5) Perpindahan jarak elektrode selalu sama
6) Pengukuran pada daerah yang relatif datar dan pada waktu tidak hujan.
7) Jumlah titik pengukuran merata dengan cara grid.
8) Arah bentangan pengukuran harus sejajar dengan arah perlapisan batu
atau tanah.
9) Pengukuran di sekitar sungai atau pantai, arah bentangan harus sejajar
pantai atau sungai.
10) Arah bentangan pengukuran harus diusahakan pada lokasi yang tidak
terpengaruh oleh benda-benda yang dapat mempengaruhi ketelitian
pengukuran (seperti rel kereta api, saluran pipa, saluran kawat listrik).
11) Apabila persyaratan pada huruf j) tidak bisa dipenuhi, maka arah
bentangan harus memotong tegak lurus benda yang mempengaruhi
tersebut.
12) Bila ada sumur bor yang berdekatan dengan lokasi pengukuran, tentukan
lokasi sumur bor di peta, catat log bornya dan lakukan pengukuran pada
lokasi sumur bor untuk pembanding.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
28 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
4.3 Prosedur Pengukuran
Prosedur pengukuran dalam konfigurasi pole dipole memiliki tahapan sebagai
berikut:
a) Tentukan titik pengukuran.
b) Gambar titik pengukuran di peta.
c) Tentukan arah bentangan pengukuran.
d) Isilah tabel pengukuran meliputi:
1) Nomor titik pengukuran;
2) Lokasi pengukuran (kampung, desa);
3) Elevasi muka tanah;
4) Tanggal, bulan dan tahun pengukuran;
5) Nama operator;
6) Nama pengawas;
7) Nama penanggung jawab.
e) Pasang elektrode potensial (P1 dan P2) pada jarak yang terpendek minimal 0,5
m dan pasang elektrode arus (C1 dan C2) dengan jarak tak hingga.
f) Hubungkan elektrode C1 dan C2 ke alat pengirim arus.
g) Hubungkan elektrode P1 dan P2 ke pengukur potensial pada alat geolistrik.
h) Catat besar arus yang dikirim dalam ampere.
i) Catat besar tegangan dalam volt atau besar tahanan listrik dalam ohm.
j) Pindahkan elektrode arus pada jarak yang tak hingga.
k) Ulangi kegiatan serupa dari e) sampai j) untuk jarak elektrode berikutnya (Tabel
3.1).
l) Bila ada sumur bor yang berdekatan dengan lokasi pengukuran, gambarkan
lokasi sumur bor pada peta dan catat bor lognya.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 29
4.4 Perhitungan
Perhitungan tahanan jenis dengan menggunakan rumus-rumus berikut:
Tahanan jenis semu:
ρa = 2 πb(a+b)
a V
I…………………………………………… (3.1)
Keterangan :
ρa adalah tahanan jenis semu (Ωm)
b adalah jarak elektrode C1 ke P1
a adalah jarak elektrode P1 ke P2
V adalah potensial
I adalah arus
π adalah konstanta bernilai 3.142
Contoh Soal :
Berapakah tahanan jenis semu jika diketahui potensial 1 A dan arus listrik adalah
1,5 A, jarak elektroda C1 ke P1 25 meter, jarak elektroda P1 ke P2 30 meter ?
Jawab :
Diketahui :
a = 25 m
b = 30 A
V = 1 A
I = 0,15 A
Ditanyakan :
ρa ?
Jawab :
ρa = 2 x 3,14230(25 + 30)
25
1
1,5
ρa = 273,73 Ωm
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
30 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
4.5 Pemodelan dan Interpretasi
Pemodelan dan interpretasi dengan menganalisis data hasil pengukuran dengan
tahapan sebagai berikut:
a) Lakukan pemodelan menurut ketentuan yang berlaku
1) Pemodelan tidak langsung adalah penyesuaian lengkung lapangan
dengan lengkung baku sesuai data yang didapat. penyesuaian lengkung
tersebut menggunakan legkung baku dan lengkung bantu.
2) Pemodelan langsung adalah pemodelan menggunakan software
Res2Dinv.
3) Tentukan nilai dan ketebalannya untuk setiap lapisan.
b) Lakukan pendugaan air tanah dengan menganalisis data hasil pemodelan dan
interpretasi untuk mendapatkan keadaan geologi bawah permukaan dan
kondisi air tanahnya, dengan tahapan sebagai berikut:
1) Urutan lapisan batuan secara tegak dari lengkung setiap titik pengukuran.
2) Tentukan jenis litologi batuan berdasarkan tahanan jenisnya sesuai
dengan tabel 3.1.
3) Tentukan batas lapisan batuan secara tegak dan bila ada dengan bor log
sumur di sekitar titik pengukuran.
4) Korelasikan hasil pendugaan setiap titik pengukuran dengan titik-titik
pengukuran lainnya, dan dengan bor log sumur yang di sekitar lokasi
pengukuran untuk dibuat penampang geologi bawah permukaan.
5) Lakukan interpretasi kedudukan lapisan yang mengandung air tanah atau
akuifer berdasarkan nilai tahanan jenisnya.
6) Perhatikan kondisi geohidrologi di daerah pengukuran dalam interpretasi
akuifer.
7) Tentukan lapisan batuan yang mengandung air tanah atau akuifer.
4.6 Laporan
Laporan pengukuran dibuat dalam satu buku yang berisi data yang diperlukan,
meliputi:
a) Keadaan geologi permukaan di daerah penyelidikan, bila ada.
b) Penampang geologi berdasarkan harga tahanan jenis dari hasil interpretasi
dalam bentuk simbol yang meliputi:
1) Satuan lapisan batuan dengan batas vertikal dan lateral.
2) Struktur geologi.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 31
c) Kondisi air tanah hasil analisis dari sifat keairan nya batu atau tanah terhadap
geologi permukaan.
d) Penentuan untuk lokasi titik pengeboran uji yang sangat diperlukan oleh
pemakai data.
e) Laporan ini ditandatangani ole petugas dari instansi yang berwenang.
4.7 Latihan
1. Sebutkan kelemahan konfigurasi pole dipole!
2. Sebutkan tiga peralatan konfigurasi pole dipole!
3. Sebutkan kedalaman investigasi pole dipole!
4.8 Rangkuman
Tata cara pengukuran geolistrik pole dipole untuk eksplorasi air tanah digunakan
sebagai acuan dan pegangan dalam menentukan jenis batu atau tanah, batas
lapisan, ketebalan dan menduga akuifer berdasarkan tahanan jenisnya.
Konfigurasi pole dipole adalah konfigurasi dengan salah satu elektrode potensial
dan elektrode arusnya dibentangkan dengan jarak tak hingga, atau C1 dan P2 tak
hingga, dimana jarak antara B-M atau C2-P1 adalah a.
Ada lima tahapan dalam survei geolistrik konfigurasi pole dipole yaitu Peralatan,
persyaratan survei, prosedur pengukuran survei, perhitungan pemodelan,
interpretasi.
4.9 Evaluasi
1. Konfigurasi pole-dipole memiliki penetrasi yang lebih dalam ……. dibandingkan
konfigurasi dipole-dipole
a. ± 65%
b. ± 60%
c. ± 75%
d. ± 80%
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
32 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
2. Pengertian konfigurasi elektrode pole dipole adalah.....
a. Konfigurasi yang memiliki jarak elektrode arus dan potensial yang sama.
Sehingga pada saat pemindahan elektrode potensial maka elektrode arus
akan pindah.
b. Konfigurasi dengan salah satu elektrode potensial dan elektrode arusnya
dibentangkan dengan jarak tak hingga, atau C1 dan P2 tak hingga, dimana
jarak antara B-M atau C2-P1 adalah a.
c. Konfigurasi yang memiliki kuat sinyal yang tinggi sehingga dapat digunakan
pada saat noise yang tinggi
d. Konfigurasi yang memiliki elektrode arus yang jaraknya di batasi oleh jarak
elektrode potensial
3. Penempatan awal elektrode untuk Konfigurasi Pole Dipole adalah.....
a. Elektroda arus mempunyai jarak yang sama dengan jarak elektroda
potensial
b. Elektroda arus jarak nya lebih panjang dua kali dari jarak elektroda
potensial
c. Elektrode arus terletak tak hingga diluar jalur rencana pengukuran
d. Elektroda arus jarak nya lebih pendek dua kali dari jarak elektroda potensia
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 33
BAB V
PERALATAN SURVEI
5.1 Jenis – Jenis Alat Survei
Resistivity meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur geolistrik
tahanan jenis. Sedangkan alat untuk mengukur geolistrik Induced Polarization (IP)
adalah IP Meter. Beberapa contoh model alat resistivity meter, yaitu:
a) AGI Mini Sting R1
Gambar 5.1. AGI Mini Sting R1 (agusia.com)
Tabel 5.1. Spesifikasi AGI Mini Sting R1 (agusia.com)
Rentang perhitungan 400 kΩ sampai 0.1 miliΩ (resistansi)
0-500 V voltase skala penuh
Resolusi perhitungan Maks 30nV, tergantung pada level voltase
Resolusi layar digit dalam notasi teknik
Keluaran intensitas
arus
1-2-5-10-20-50-100-200-500 mA.
Input Impedansi >150 MOhm
Input voltase Maks 500 V
Indikator Hasil Belajar:
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan peralatan survei.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
34 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
Tipe perhitungan IP Chargeability domain waktu, Perhitungan slot 6x dan
disimpan di memori
Transmisi arus IP ON+, OFF, ON-, OFF
Banyaknya Siklus Waktu perhitungan dasar, 1.2, 3.6, 7.2 atau 14.4 s
sesuai yang dipilih oleh pengguna melalui keyboard.
Rentang otomatis dan penambahan komutasi sekitar
1.4s
Pengurangan noise Lebih dari 100dB pada f>20Hz
Kalibrasi Sistem Kalibrasi dilakukan secara digital oleh
microprocessor berdasarkan nilai koreksi yang
disimpan dalam memori
Penyimpanan Data Pembacaan rata-rata resolusi penuh dan error
disimpan bersamaan dengan user memasukkan
koordinat dan waktu serta hari untuk setiap
pengukuran
Kapasitas Memori Memori dapat menyimpan lebih dari 3000
pengukuran pada memori internal
Siklus IP 1 s, 2 s, 4 s dan 8 s
Pengukuran Manual Instrumen memiliki 4 banana pole screws untuk
menghubungkan elektrode arus dan potensial
selama pengukuran resistiviti manual
Kontrol user 20 tombol, keyboard tahan segala cuaca dengan
tombol numerik dan fungsi tombol on/off, tombol
pengukur, terhubung dengan keyboard utama
Power supply (kantor) 12V, 4.5 Ah NiMH dengan baterai yang dapat
dicharger ulang
Charger baterai Charger dual stage dengan input yang dapat ditukar
(115/230 V AC @ 50/60 siklus)
Berat 6.6 kg (14.5 lb.)
Dimensi lebar 255mm (10"), panjang 255 mm (10") dan tinggi
123 mm (5")
Power supply
(lapangan)
12V or 2x12V DC external power (satu atau dua 12V
baterai), konektor pada panel depan.
Hasil daya maksimum meningkat menggunakan
sumber2x12V
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 35
Rentang Input
tambahan
Otomatis, selalu menggunakan rentang dinamik
penuh dari receiver.
Keluaran Voltase 800 Vp-p, voltase elektrode sebenarnya tergantung
arus tertransmisi dan resisitivitas tanah
Waktu Operasi Tergantung pada kondisi, rangkaian dalam auto
mode dapat menyesuaikan arus untuk menyimpan
energi. Pada keluaran arus 20mA dan resistansi
elektrode 10kW dapat melakukan 2000 siklus saat
baterai dicharger full
b) AGI Super Sting R8
Gambar 5.2. AGI Super Sting R8 (agusia.com)
Tabel 5.2. Spesifikasi AGI Super Sting R8 (agusia.com)
Rentang perhitungan +/- 10V
Resolusi perhitungan Maks 30nV, tergantung pada level voltase
Resolusi layar 4 digit dalam notasi teknik
Keluaran intensitas
arus
1mA – 2000mA berkelanjutan, dihitung hingga akurasi
tinggi
Keluaran Voltase 800 Vp-p, voltase elektrode sebenarnya tergantung arus
tertransmisi dan resisitivitas tanah
Input Impedansi 200W
Kompensasi SP 8 channel
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
36 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
Input Impedansi Otomatis, selalu menggunakan rentang dinamik penuh dari
receiver
Input Impedansi >150 MOhm
Transmisi arus IP ON+, OFF, ON-, OFF
Siklus IP 0.5, 1, 2, 4, dan 8 s
Pengurangan noise Lebih dari 100dB pada f>20Hz
Pengurangan noise
jaringan listrik
Lebih dari 120dB pada jaringan listrik dengan frekuensi (16
2/3, 20, 50 & 60 Hz) untuk pengukuran siklus 1.2 s atau
lebih besar
Pengukuran Manual Instrumen memiliki 4 banana pole screws untuk
menghubungkan elektrode arus dan potensial selama
pengukuran resistiviti manual
Kontrol user 20 tombol, keyboard tahan segala cuaca dengan tombol
numerik dan fungsi
Tombol on/off
Tombol pengukur, terhubung dengan keyboard utama
LCD dengan lampu malam
Temperatur
pengoperasian -5 sampai +50°C
Berat 10.2 kg (22.5 lb) instrumen saja
Dimensi lebar 184 mm (7.25"), panjang 406 mm (16") dan tinggi273
mm (10.75")
Kapasitas Memori Memori dapat menyimpan lebih dari 79.000 pengukuran
(resisistivity mode) dan lebih dari 26.000 pengukuran
apabila dikombinasikan resistivity/IP mode
Siklus resistivitas Waktu perhitungan dasar 0.2, 0.4, 0.8, 1.2, 3.6, 7.2, atau
14.4 s sesuai yang dipilihi oleh pengguna melalui keyboard.
Rentang otomatis dan penambahan komutasi sekitar 1.4s
Display LCD display (16 baris x 30 karakter) dengan lampu malam
Power supply
(lapangan)
12V or 2x12V DC external power (satu atau dua 12V
batere), konektor pada panel depan.
Hasil daya maksimum meningkat menggunakan sumber
2x12V
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 37
c) ABEM SAS 1000/4000
Gambar 5.3. ABEM SAS 1000/4000 (geoelectric.ru)
Tabel 5.3. Spesifikasi ABEM SAS 1000/4000 (geoelectric.ru)
Output Power 250 W
Current transmission True Current Transmitter
Output Current Accuracy Better than 0.4%
Maximum Output Current 2500mA
Maximum Output Voltage +/- 600V, 1200V peak to peak
Instant Polarity Changer YES
Accuracy 0.4%
Precision 0.1%
Self Diagnostics Temperature, Power dissipation, Monitoring
Safety Emergency Interrupter easily accessible
No. of Channels 4,8 or 12 input (+ 2 for Tx monitoring
Isolation All channels are galvanically separated
Input Voltage Range +/- 600V
Input impedance 200M Ohm
Precision 0.1%
Accuracy 0.2%
Linearity 0.005%
Range
+/- 2.5V , 200 M Ohm
+/- 15V , 30 M Ohm
+/- 600V , 20 M Ohm
Flat Frequency Response Better than 1% up to 300Hz
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
38 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
Resolution Theoritical 3 nV at 1 secintegration
Full wave form
Sampled and average to requested data.
Possible to activate recording to file for post
analysis
Dynamic Averaging 24 bit A/D conversion
Data Sampling Rate 30kHz
Cycle time From 0.4 sec to 28,7 sec User selectable,
resistivity
Pulse time from 0.1 sec to 8.2 sec. User selectable
Voltage +/- 600V
Current +/- 2500 mA
Full waveform monitored
Current Accuracy 0.2%
Current Precision 0.1%
Voltage +/- 600V
Current +/- 2500 mA
Full waveform monitored
Current Accuracy 0.2%
Current Precision 0.1%
Service point Accessible through Internet, Multifunction
connector
Memory Capacity 8GB, More than 1 500 000 readings
Power
8 Ah Internal NiMH
12V power pack andExternal 12 VDC
battery (recommended option for all
Imaging and VES)
Dimensions (WxLxH) 39x21x32cm
Weight 12 kg
Ambient Temperature Range -20°C to + 70°C operating ¹·²
-30°C to + 80°C storage³
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 39
d) OYO Mc Ohm Mark 2
Gambar 5.4. OYO Mc Ohm Mark 2 (oyo.co.jp)
Tabel 5.4. Spesifikasi OYO Mc Ohm Mark 2 (oyo.co.jp)
Input Impedance 10 OM-ohm
Measurement Potential 25 mV, 250 mV, 3500 mV
Resolution 1 uV
S/N ratio 90 dB (50/60 Hz)
Stack Count 1, 4, 16, 64
Time of one measurement cycle 3,7 sec
Input Voltage 400 Vpp
Output Current 1, 2, 5, 10, 100, 200 mA
Operating Voltage 12 VDC
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
40 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
e) Resistivity Meter Naniura NRD 300 HF
Gambar 5.5. Resistivity Meter Nainura NRD 300 HF (alatukurteknik.com)
Tabel 5.5 Spesifikasi Resistivity Meter Nainura NRD 300 HF
(alatukurteknik.com)
Power supply DC in 12 Volt
Power Output 300 watt for >20A
Output Voltage 500 V maximum
Output Current 2000 mA maximum
Current accuracy 1 mA
Reading Type Digital
Power for Digital Meter 9 V, dry battery
Input impendency 10 M-ohm
Range 0,1 mV up to 500 V
Accuracy 0,1 mV
Compensator (Rough) 10 x turn
Compensator (Smooth) 1 x turn
Power for Digital Meter 3 Volt
Reading Facility HOLD
Weight 6 kg
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 41
f) G-Sound
Gambar 5.6. G-Sound (geocis.com)
Tabel 5.6. Spesifikasi G-Sound (geocis.com)
Tegangan 400 V (100mA)
Tegangan Max 500 V
Arus 100 mA (Rab < 4k ohm) constant current
Daya 75 W by 2 x 12 V NiCad Baterai
Impedance 10 MOhm (high impedance)
Resolusi 12 bit (high resolution)
Kedalaman analisa > 150 m (moist soil)
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
42 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
g) IRES T300F
Gambar 5.7. IRES T300F (gfinstruments.cz)
Tabel 5.7. Spesifikasi IRES T300F (gfinstruments.cz)
Catu Daya/ DC in (Power Supply) 12 Volt, minimal 6 AH (Untuk power maksimum
gunakan accu basah)
Daya (Power output) 300 Watt untuk catu daya > 20 A
Tegangan Keluar (Output Voltage) 500 V maksimum
Arus keluar (Output Current) 2000 mA maksimum
Ketelitian arus 1 mA
Sistem Pembacaan Digital
Catu Daya Digital Meter 9 Volt, Baterai Kering
Fasilitas Current Loop Indicator
Fasilitas Current Loop Indicator
Impendansi Masukan
(Input Impedantion) 10 M-ohm
Kompensator Kasar 10 x putar (Precission Multi Turn Potensiometer)
Kompensator Halus 1 x putar (Wire Wound Resistor)
Sistem pembacaan Digital (Auto Range)
Catu daya digital meter 3 Volt (2 buah baterai kering ukuran AA)
Batas Ukur Pembacaan 0,1 mV hingga 500 Volt
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 43
h) ARES GF INSTRUMENT
Gambar 5.8. ARES GF INSTRUMENT (geoelectric.ru)
Tabel 5.8. Spesifikasi ARES GF INSTRUMNET (geoelectric.ru)
Power Up to 300 W
Current Up to 2.0 A
Voltage 10-550 V (1100 Vp-p)
Protection Full electronic protection
Precision 0.1 %
Input impedance 20 MΩ
Input voltage range ±5 V
Mains frequency filtering 50 or 60 Hz
Precision 0.1 %
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
44 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
5.2 Kelebihan (Manfaat) Alat Survei
a) AGI Mini Sting R1
1) Harga lebih murah dari Super Sting.
2) Ukuran yang kecil (sudah termasuk baterai) membuat mudah untuk
dibawa-bawa.
3) Menu sistem pada mini sting mudah untuk digunakan.
4) Dapat digunakan dalam konfigurasi yang berbeda-beda.
5) Dapat digunakan secara manual dan otomatis (tambahan swift box).
6) Dapat digunakan pada medan yang tidak datar.
b) Supersting R8 IP
1) Memiliki kemampuan mengukur 8 channel secara simultan sehingga
menghemat waktu di lapangan secara drastis.
2) Dapat menggunakan 12V dan 24V.
3) Dapat mengukur pada medan yang tidak datar.
4) Dapat digunakan pada berbagai macam konfigurasi.
5) Tingkat akurasi data sangat tinggi.
6) Level noise sangat rendah.
7) Memiliki kapasitas memori internal yang besar untuk menyimpan data hasil
perhitungan.
c) ABEM SAS 1000/4000
1) Jika dioperasikan pada suhu yang sangat tinggi dan terjadi overheating.
Alat akan mati secara otomatis.
2) Mudah di bawa karena ada handelnya.
3) Hasil resistivitas akan ter display dalam bentuk tabel sehingga saat di
lapangan kita tidak susah dalam mencatat.
4) Alat dapat memperlihatkan penampang pseudosection.
5) Alat dapat memperlihatkan kurva VES.
6) Memiliki receiver GPS.
7) Layar yang sudah terdisplay berwarna sehingga layarnya bukan monokrom
(hitam putih).
8) Ada tanggal dan informasi waktu pada status bar.
9) Memiliki keyboard internal dan eksternal.
10) Baterai dan suhu dapat dikontrol secara langsung.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 45
d) OYO Mc OHM Mark 2
1) Cara mengoperasikannya mudah, cocok untuk pemula.
2) Bisa melakukan stacking berkali-kali untuk keakuratan data.
3) Data yang didapatkan bagus dan akurat.
e) Nainura NRD 300 HF
1) Sudah menggunakan kartu PCB terpisah untuk setiap skala tegangan yang
diinjeksikan.
2) Berat Naniura NRD 300 HF lebih ringan daripada NRD 22 yang masih
menggunakan transformator.
3) Bila terjadi kerusakan pada transormer maka satu skala pengukuran saja
yang terganggu.
f) G-Sound
1) Pengukuran dapat di upgrade melalui komputasi.
2) Ringan dan portable (bertanya hanya 1 kg, tidak termasuk baterai).
3) 100 mA current source.
4) Anti short circuit.
5) Long life battery (hemat arus).
6) Bisa digunakan untuk pengukuran sounding atau profiling/mapping
resistivitas.
7) Bisa digunakan untuk pengukuran dalam skala laboratorium.
8) Murah dan handal.
9) Ringan dan portable.
10) Sangat presisi dan akurat.
11) Hemat arus.
12) Mendukung semua keperluan baik di lapangan maupun laboratorium.
g) IRES T300F
1) Daya akurasi tinggi dengan hasil memuaskan.
2) Lebih ringan.
3) Relatif lebih murah.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
46 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
h) ARES
1) Merupakan generasi terbaru dalam alat geolistrik.
2) Dapat mengukur 10 channel IP Windows secara simultan.
3) Alat lebih ringan dari super sting (5,9kg) sehingga memudahkan untuk
dibawa kemana saja.
4) Tahan terhadap suhu cuaca (-10oC sampai 60 oC).
5) Dapat digunakan dalam 3 Dimensi.
6) Hasil pengukuran lebih akurat.
7) Tidak perlu disambungkan ke PC.
8) Pengaplikasian alat lebih luas (eksplorasi air tanah, penyelidikan geoteknik,
pemantauan bendungan dan tanggul, studi lingkungan, pollution plumes
mapping, survei geologi, prospeksi mineral, arkeologi).
5.3 Kelemahan Alat Survei
a) AGI Mini Sting R1
1) Saat melakukan stacking harga rho apparent (resistivitas semu) selalu
berubah-ubah. Diperlukan waku >5 menit hingga angkanya konstan.
2) Alat perlu di kalibrasi ulang karena sering menunjukkan harga rho apparent
(resistivitas semu) yang negatif.
3) Hanya dapat menggunakan 12 V.
b) Supersting R8 IP
1) Jika terdapat nilai resistivitas yang menyimpang tidak dapat di reset lagi
prosesnya.
2) Ukurannya yang besar membuat tidak praktis di bawa-bawa.
3) Jika terdapat satu kabel yang rusak maka kabelnya tidak dapat digunakan
karena kabelnya saling terhubung.
c) ABEM SAS 1000/4000
1) Memiliki harga yang relatif lebih mahal.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 47
d) OYO Mc OHM Mark 2
1) Tidak dapat menjalankan perhitungan secara otomatis, jadi perhitungan
dilakukan secara manual.
2) Tidak ada lampu pada layar sehingga jika pengambilan data diambil di
malam hari akan tidak terlihat.
3) Layar masih monokrom.
e) Nainura NRD 300 HF
1) Banyak menggunakan komponen pasif sehingga bisa dibilang lebih ‘robust’
dan ‘sturdy’.
2) Masih menggunakan analog kompensator untuk menetralisir efek SP (Self
Potensial), sehingga membutuhkan waktu dan ketelitian surveior saat
menetralisir nilai SP.
f) G-Sound
1) Pengukuran hanya bsa dilakukan secara manual dan tidak otomatis.
2) Pengukurannya lebih lama dari pada multi channel.
3) Konversi data secara manual.
g) IRES T300F
1) Memerlukan waktu yang lama saat pengambilan data.
2) Pengambilan data dilakukan secara manual.
5.4 Hambatan dan Penggunaan Alat Survei
a) Penggunaan Resistivity meter:
1) Pasang elektrode sesuai konfigurasi yang diinginkan. Gunakan palu untuk
menancapkan elektrode ke dalam tanah.
2) Hubungkan elektrode arus menggunakan kabel gulung dan konektor ke C1
dan C2 pada resistivitimeter (Gambar 5.9).
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
48 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
Gambar 5.9. Tampilan Panel Resistivitimeter Nainura NRD 22S (Racka, 2014)
3) Hubungkan elektrode potensial menggunakan kabel gulung dan konektor
ke P1 dan P2 pada resistivitimeter.
4) Hubungkan baterai menggunakan kabel konektor ke jack INPUT (+) dan (-
) pada resistivitimeter. Lihat jarum indikator Batt hingga menunjuk ke
bagian merah di kanan. Hal ini menunjukkan baterai dalam keadaan penuh
(tegangan memadai). Jika tidak, baterai perlu diisi (discharge) hingga
penuh, sebelum digunakan.
5) Putar tombol Power ke kanan dari OFF menjadi ON, maka resistivitimeter
sudah dinyalakan. Lihat jarum indikator Current Loop hingga menunjuk ke
bagian merah di kanan. Hal ini menunjukkan kontak elektrode arus dengan
tanah (bumi) dan resistivitimeter sudah cukup memadai. Jika tidak, perbaiki
koneksinya, tancap elektrode arus lebih dalam atau siram tanah di sekitar
elektrode arus dengan air atau larutan elektrolit untuk memperbaiki kontak.
6) Putar tombol OUTPUT dari angka 0 ke angka yang dikehendaki. Makin
besar angka yang dipilih (1 - 6), makin besar injeksi arus yang dihasilkan.
7) Putar Compensator Coarse, kemudian Fine hingga display tegangan V
(Autorange) menunjuk angka nol atau mendekati nol.
8) Injeksikan arus dengan menekan tombol START hingga display arus I (mA)
menunjukkan angka yang stabil.
9) Tekan tombol HOLD dan baca harga arus pada display arus I (mA) serta
harga tegangan/potensial pada display tegangan V (Autorange) sebagai
data pengukuran.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 49
10) Lakukan pengukuran beberapa kali (misal, 3 kali) untuk lebih meyakinkan
data hasil pengukuran. Catat semua hasil pengukuran, termasuk jarak
spasi elektrode (a, n) dalam tabel hasil pengukuran (Tabel 5.9)
11) Pindahkan posisi elektrode ke posisi pengukuran berikutnya. Lakukan
prosedur pengukuran yang sama seperti di atas (1-10) Lakukan hal yang
sama hingga seluruh data diperoleh sesuai rencana pengukuran.
Tabel 5.9. Data Hasil Pengukuran Lapangan (Racka, 2014)
No a n V I V/I k psemu Keterangan
1
2
3
4
.
.
n
b) Standar Operasional Penggunaan Alat
1) Ketika mengatur instrumen jangan hubungkan kabel swift ke instrumen
sebelum benar-benar dimulai proses pengukuran.
2) Jangan pernah operasikan alat jika diketahui ada bagian yang rusak
3) Jangan operasikan alat ini dibawah cuaca badai. Cuaca badai akan sangat
membahayakan alat dan manusia yg mengoperasikan. Karena alat ini
mengandung rangkaian CMOS yang sensitif dan dapat rusak oleh
pencahayaan sekitar. Dan untuk keselamatan pekerja disarankan tidak
untuk berdiri di dekat ujung kabel konduktif saat terjadi badai.
4) Untuk menghindari bahaya potensial, gunakanlah alat ini sesuai dengan
kegunaannya.
5) Selalu cek keadaan kabel swift dan kabel penghubung, jika ada yg rusak
langsung diganti dengan yg masih bagus.
c) Standar Operasional Pengukuran
1) Pastikan tidak ada komponen-komponen lain yang dapat mengganggu
disekitar garis survei dan tidak ada yang menyentuh elektrode saat
pengukuran.
2) Jangan sentuh komponen penghubung apapun saat pengukuran dimulai.
3) Tidak disarankan bekerja sendirian.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
50 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
4) Jagalah elektrode agar tidak ada yang menyentuhnya saat alat
dioperasikan.
5) Pakailah sepatu sol karet dan sarung tangan berbahan karet ketika
menyetting kabel.
6) Garis survei harus diberi tanda agar dapat dengan mudah terlihat.
7) Lakukan langkah-langkah setting garis survei secara berurutan dengan
hati-hati. Pertama tancapkan dahulu elektrode ke tanah, kemudian julurkan
kabel Swift. Pastikan kabel elektrode tidak terhubung pada instrumen
sebelum dimulai proses pengukuran.
d) Gangguan Pada Saat Pengukuran (noise)
Adapun gangguan yang mungkin terjadi pada saat kita melakukan pengukuran
geolistrik yaitu:
1) Hujan apabila pada saat hujan kita melakukan pengukuran itu sangat
mengganggu karena yang kita ukur adalah kuat arus atau listrik dalam
bumi. Jika ada air maka arus listrik besar sehinnga sangat mempengaruhi
pada data yang kita butuhkan.
2) Petir pada saat kita mengukur geolistrik dalam tanah pada saat ada petir
ini sangat mengganggu, karena kita menggunakan alat hampir semua
terbuat dari besi, jadi kemungginan kita bisa tersambar petir. Ini sangat
mengganggu pada proses pengukuran dan pada data kita.
3) Gempa Bumi merukapan peristiwa alam berupa getaran atau gerakan
bergelombang pada kulit bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen. Jika
kita melakukan pengukuran pada saat gempa bumi tentu data yang kita
dapat tidak akurat. Karena getaran atau gerakan yang terjadi dapat
menggeserkan alat yang kita pasang dengan jarak yang telah ditentukan,
sehingga jika hal itu terjadi maka kita harus mengukur kembali.
5.5 Kalibrasi Alat Survei
Kalibrasi dilakukan pada tahap awal sebelum melakukan akuisisi data lapangan.
Kalibrasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan alat yang dipakai dimana
hasil yang didapatkan berupa berapa persen keakuratan alat dalam mengukur
berbagai nilai hambatan (ohm) yang telah ditentukan. Keakuratan alat memiliki nilai
toleransi antara 95% - 105 %. Kalibrasi dilakukan sebelum melakukan sesuatu
akuisisi data lapangan. Harga resistivitas yang didapatkan dari akuisisi data
lapangan akan dikalibrasikan dengan persen keakuratan alat sehingga yang akan
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 51
didapatkan adalah data yang lebih akurat. Jenis Resistivitymeter yang Digunakan
dalam kalibrasi ini adalah Naniura Model NRD 22 S. Berikut adalah tabel harga nilai
hambatan setiap chanel nya .
Tabel 5.10. Harga Nilai Hambatan (ohm) (Dzikru, 2015)
Naniura Model NRD 22
Resistivitymeter model ini dapat membaca besarnya harga SP, dimana nantinya
dalam pengukuran SP harus dinolkan terlebih dahulu. Instrumen alatnya adalah
sebagai berikut:
Gambar 5.10. Instrumen Resistivitymeter Nainura Model NRD 22 (Dzikru, 2015)
Chanel Ohm
0 Tak Hingga
2 0.22
3 0.47
4 1.47
5 4.7
6 10
Chanel Ohm
6 22
7 100
8 220
9 470
10 1000
11 4700
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
52 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
a) Peralatan dan Perlengkapan
Alat yang digunakan adalah resistivitymeter dengan tipe atau jenis Naniura
model NRD 22 S.
Alat tambahan yang digunakan, antara lain:
1) Accu 12 volt
Digunakan sebagai sumber daya selama kalibrasi dilakukan.
2) Multimeter
Digunakan untuk mengukur tahanan jenis dan tegangan potensial pada alat
accu.
3) Kalibrator
Digunakan untuk mengkalibrasi alat sebelum akuisisi di lapangan.
4) Kabel Konektor
Sebagai alat yang menghubungkan accu-kalibrator-resistivitymeter.
Gambar 5.11. Instrumentasi Alat yang Digunakan (Dzikru, 2015)
Langkah-langkah dalam pengambilan data kalibrasi resistivitymeter yaitu:
a) Menyiapkan alat-alat survei.
b) Menghubungkan alat ke accu dan kalibator dengan kabel konektor
c) Mengukur potensial pada channel 3.
d) Menyalakan resistivitymeter.
e) Memutar course dan fine untuk menolkan bacaan auto range.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 53
f) Menekan tombol START sampai pembacaanya konstan, kemudian tekan
HOLD.
g) Mencatat data yang terbaca berupa volt dan ampere.
h) Mematikan resistivitymeter Naniura.
i) Mengolah data yang didapat, melakukan berulang-ulang hingga channel 10.
Langkah-langkah dalam pengolahan data dalam kalibrasi resistivitymeter
adalah:
a) Dari nilai V dan I yang terukur pada alat didapatkan nilai R dengan perhitungan
manual, harga R didapatkan hasil bagi antara nilai V yang terukur dengan nilai
I.
b) Kemudian menghitung nilai Rho rerata.
c) Nilai Rho rerata dibagi dengan nilai ohm channel kemudian dikalikan dengan
100% untuk mendapatkan persentase.
d) Menghitung ohm toleransi 95% dan ohm toleransi 105% untuk setiap channel
(channel 3-10).
e) Membuat grafik kalibrasi yaitu ohm channel Vs ohm channel, ohm channel Vs
ohm rerata, ohm channel vs toleransi 95% , ohm channel vs toleransi 105%.
5.6 Latihan
1. Sebutkan empat alat pengukuran survei!
2. Sebutkan kelebihan alat survei SAS 300 C!
3. Sebutkan standar aksesoris yang di gunakan untuk alat survei ARES!
5.7 Rangkuman
Resistivity meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur geolistrik
tahanan jenis. Sedangkan alat untuk mengukur geolistrik Induced Polarization (IP)
adalah IP Meter. Beberapa contoh model alat resistivity meter, yaitu, AGI Mini Sting
R1, AGI Super Sting R8, ABEM SAS 1000/4000, OYO McOhm Mark 2, Nainura
NRD 300HF, G-Sound, IRES T300F, dan ARES GF INSTRUMNENT.
Kalibrasi dilakukan pada tahap awal sebelum melakukan akuisisi data lapangan.
Kalibrasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan alat yang dipakai dimana
hasil yang didapatkan berupa berapa persen keakuratan alat dalam mengukur
berbagai nilai hambatan (ohm) yang telah ditentukan Keakuratan alat memiliki nilai
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
54 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
toleransi antara 95% - 105 %. Kalibrasi dilakukan sebelum melakukan sesuatu
akuisisi data lapangan.
Alat survei untuk mengukur geolistrik tahanan jenis masing-masing memiliki
kelebihan, kekurangan serta spesikfikasi yang berbeda.
5.8 Evaluasi
1. Input Impedansi Spesifikasi AGI Mini Sting R1 adalah…..
a. >150 MOhm
b. >200 MOhm
c. >250 MOhm
d. >350 MOhm
2. Kelebihan Supersting R8 IP adalah…..
a. Harga lebih murah dari Super Sting
b. Memiliki kemampuan mengukur 8 channel secara simultan sehingga
menghemat waktu di lapangan secara drastis
c. Menu sistem pada mini sting mudah untuk digunakan
d. Dapat digunakan dalam konfigurasi yang berbeda-beda
3. Kelemahan Nainura NRD 300 HF adalah…..
a. Tidak dapat menjalankan perhitungan secara otomatis, jadi perhitungan
dilakukan secara manual.
b. Tidak ada lampu pada layar sehingga jika pengambilan data diambil di
malam hari akan tidak terlihat
c. Masih menggunakan analog kompensator untuk menetralisir efek SP (Self
Potensial), sehingga membutuhkan waktu dan ketelitian surveior saat
menetralisir nilai SP
d. Layar masih monokrom
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 55
BAB VI
PENENTUAN DESAIN SURVEI GEOLISTRIK
6.1 Penentuan Konfigurasi Geolistrik
Sensitivitas konfigurasi geolistrik tentunya berbeda antara satu-sama lainnya.
Seperti konfigurasi Wenner yang dipakai untuk survei dangkal dan sensitif terhadap
arah horizontal (mapping). Konfigurasi schlumberger yang dipakai untuk
penyelidikan pada area mendatar atau relatif datar. Jika konfigurasi ini dika
aplikasikan pada medan tidak datar, maka dari data yang peroleh haruslah
dilakukan koreksi ulang dari hasil pengukuran yang diperoleh. Konfigurasi geolistrik
Schlumberger ini sensitif terhadap arah vertikal (sounding).
Dalam penentuan metode konfigurasi geolistrik perlu diperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a) Tipe struktur yang hendak dicari
b) Sensitivitas resistivity meter
c) Kedalaman struktur yang dicari
d) Sensitivitas array secara vertikal dan horizontal
e) Kekuatan signal
Tabel 6.1. Penentuan Konfigurasi Geolistrik (Andriyani, 2010)
Kriteria Konfigurasi Geolistrik
Wenner Schlumberger Pole Dipole
Resolusi Vertikal Baik Sedang Buruk
Kesusaian terhadap Vertical
Electrical Sounding (VES) Sedang Baik Buruk
Sensitivitas lateral
inhomogeneitas Tinggi Sedang Sedang
Interpretasi Baik Baik Sedang
Indikator Hasil Belajar:
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan penentuan desain survei geolistrik.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
56 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
6.1.1 Kawasan Karst
Pada kawasan karst masalah yang paling utama adalah masalah kekeringan dan
krisis air bersih. Pemanfaatan air oleh penduduk sekitar hanya dapat dilakukan pada
telaga yang pada umumnya berlokasi jauh dari pemukiman dan sulit dicapai. Pada
musim penghujan ketersediaan air di telaga cukup untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat sekitar, sedangkan pada musim kemarau telaga mengering. Hal inilah
yang menjadi permasalahan yang sangat kompleks yang terjadi pada kawasan
karst.
Metode geolistrik yang cocok digunakan menggunakan metode geolistrik
konfigurasi pole dipole dikarenakan elektrode arus C2 terletak jauh diluar jalur
rencana pengukuran. Sebagai contoh, jika kita melakukan pengukuran resistivity
dari titik 0 kearah kanan dari gambar ilustrasi dibawah ini sepanjang 1000 m, maka
penempatan elektrode arus C2 bisa diletakkan disisi kiri dari titik 0 sejauh 1000 m
pula kearah kiri. Seperti pada gambar berikut:
Gambar 6.1. Penempatan Awal Elektrode Arus dan Potensial pada
Konfigurasi Pole dipole (Andriyani, 2010)
6.1.2 Kawasan Pantai
Pada kawasan pantai (aluvium) yang merupakan endapan permukaan berupa
kerikil, pasir dan lanau. Batu lempung dan batu pasir dimana batu pasir dominan
berpotensi sebagai lapisan pembawa air. Kawasan pantai memiliki area yang cukup
luas dan memiliki area yang relatif datar sehingga metode yang digunakan adalah
metode resistivitas sounding konfigurasi Schlumberger.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 57
6.1.3 Kawasan Pegunungan
Pada kawasan pegunungan metode yang cocok digunakan adalah metode
resistivitas mapping konfigurasi Wenner dikarenakan Metode ini memiliki kekuatan
sinyal yang kuat sehingga dapat menjadi faktor yang penting dalam kawasan
pegunungan yang mempunyai noise yang cukup tinggi.
6.2 Prosedur Pengambilan Data
6.2.1 Peralatan Lapangan
Peralatan lapangan yang diperlukan dalam pengukuran metode geolistrik tahanan
jenis terdiri dari:
a) Resistivitymeter Nainura NRD 22-S
b) Elektrode potensial
c) Elektrode arus
d) Kabel elektrode
e) Kabel konektor
f) Baterai basah/kering
g) Palu elektrode
h) Meteran
i) Kompas bidik
j) Alat tulis
k) Tali rapiah
l) Patok
m) GPS
6.2.2 Prosedur Pemindahan Konfigurasi Elektrode
a) Konfigurasi Schlumberger
1) Pasang elektrode dengan jarak spasi elektrode yang sama (a) untuk semua
elektrode (n=1), seperti pada Gambar 6.2
2) Pengukuran pada lapisan kedua dan berikutnya (n), jarak spasi antar
elektrode arus (AB) dan antar elektrode potensial (MN) tetap (a), tetapi
jarak spasi antar elektrode arus dan potensial (BM) diperbesar menjadi
kelipatannya yaitu 2a, 3a, hingga na.
3) Hal ini bisa dilakukan sepanjang lintasan pengukuran untuk data 2D,
dengan menjadikan ujung-ujung lintasan sebagai patokan.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
58 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
Gambar 6.2. Susunan Elektrode Konfigurasi Schlumberger (Racka, 2014)
b) Konfigurasi Wenner
1) Pasang elektrode dengan jarak spasi elektrode yang sama (a) untuk semua
elektrode, seperti pada Gambar 6.3.
2) Setelah dilakukan pengukuran, jarak spasi elektrode diperbesar menjadi
kelipatannya yaitu 2a, 3a, hingga na (Gambar 6.4)
3) Hal ini bisa dilakukan sepanjang lintasan pengukuran untuk data 2D,
dengan menjadikan ujung-ujung lintasan sebagai patokan.
4) Pengubahan jarak spasi elektrode bisa diubah setiap kali pengukuran, atau
diselesaikan sepanjang lintasan baru dilakukan pengukuran untuk jarak
spasi elektrode yang berbeda.
Gambar 6.3. Susunan Elektrode Konfigurasi Wenner (Racka, 2014)
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 59
Gambar 6.4. Pengubahan Susunan Elektrode Konfigurasi Wenner (Racka,
2014)
6.3 Latihan
1. Sebutkan lima peralatan lapangan yang digunakan dalam pengambilan data!
2. Apa konfigurasi yang cocok digunakan dalam kawasan karst?
3. Apa konfigurasi yang cocok digunakan dalam kawasan pantai?
6.4 Rangkuman
Sensitivitas konfigurasi geolistrik tentunya berbeda antara satu-sama lainnya.
Seperti konfigurasi Wenner yang dipakai untuk survei dangkal dan sensitif terhadap
arah horizontal (mapping). Konfigurasi schlumberger yang dipakai untuk
penyelidikan pada area mendatar atau relatif datar. Jika konfigurasi ini dika
aplikasikan pada medan tidak datar, maka dari data yang peroleh haruslah
dilakukan koreksi ulang dari hasil pengukuran yang diperoleh. Konfigurasi geolistrik
Schlumberger ini sensitif terhadap arah vertikal (sounding).
Dalam penentuan metode konfigurasi geolistrik perlu diperhatikan adalah tipe
struktur yang hendak dicari, sensitivitas resistivity meter, kedalaman struktur yang
dicari, sensitivitas array secara vertikal dan horizontal, kekuatan signal.
Metode geolistrik yang cocok digunakan pada kawasan karst menggunakan metode
geolistrik konfigurasi pole dipole dikarenakan elektrode arus C2 terletak jauh diluar
jalur rencana pengukuran.
Kawasan pantai memiliki area yang cukup luas dan memiliki area yang relatif datar
sehingga metode yang digunakan adalah metode resistivitas sounding konfigurasi
Schlumberger. Pada kawasan pegunungan metode yang cocok digunakan adalah
metode resistivitas mapping konfigurasi Wenner dikarenakan Metode ini memiliki
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
60 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
kekuatan sinyal yang kuat sehingga dapat menjadi faktor yang penting dalam
kawasan pegunungan yang mempunyai noise yang cukup tinggi.
6.5 Evaluasi
1. Resolusi vertikal konfigurasi geolistrik Wenner adalah…..
a. Baik
b. Sedang
c. Buruk
d. Tinggi
2. Berikut ini yang perlu diperhatikan dalam penentuan metode konfigurasi
geolistrik, kecuali…..
a. Tipe struktur yang hendak dicari
b. Kekuatan peralatan
c. Sensitivitas resistivity meter
d. Kedalaman struktur yang dicari
3. Metode geolistrik yang cocok digunakan pada kawasan karst adalah…..
a. Metode geolistrik konfigurasi Schlumberger
b. Metode geolistrik konfigurasi Wenner
c. Metode geolistrik konfigurasi Pole Dipole
d. Metode geolistrik konfigurasi Dipole Dipole
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 61
BAB VII
PENUTUP
7.1 Simpulan
Tata cara pengukuran geolistrik Schlumberger untuk eksplorasi air tanah digunakan
sebagai acuan dan pegangan dalam menentukan jenis batu atau tanah, batas
lapisan, ketebalan dan menduga akuifer berdasarkan tahanan jenisnya.
Tata cara pengukuran geolistrik Wenner untuk eksplorasi air tanah digunakan
sebagai acuan dan pegangan dalam menentukan jenis batu atau tanah, batas
lapisan, ketebalan dan menduga akuifer berdasarkan tahanan jenisnya.
Konfigurasi pole dipole adalah konfigurasi dengan salah satu elektrode potensial
dan elektrode arusnya dibentangkan dengan jarak tak hingga, atau C1 dan P2 tak
hingga, dimana jarak antara B-M atau C2-P1 adalah a.
Resistivity meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur geolistrik
tahanan jenis. Sedangkan alat untuk mengukur geolistrik Induced Polarization (IP)
adalah IP Meter. Beberapa contoh model alat resistivity meter, yaitu, AGI Mini Sting
R1, AGI Super Sting R8, ABEM SAS 1000/4000, OYO McOhm Mark 2, Nainura
NRD 300HF, G-Sound, IRES T300F, dan ARES GF INSTRUMNENT.
Sensitivitas konfigurasi geolistrik tentunya berbeda antara satu-sama lainnya.
Seperti konfigurasi Wenner yang dipakai untuk survei dangkal dan sensitif terhadap
arah horizontal (mapping). Konfigurasi schlumberger yang dipakai untuk
penyelidikan pada area mendatar atau relatif datar. Jika konfigurasi ini dika
aplikasikan pada medan tidak datar, maka dari data yang peroleh haruslah
dilakukan koreksi ulang dari hasil pengukuran yang diperoleh. Konfigurasi geolistrik
Schlumberger ini sensitif terhadap arah vertikal (sounding).
7.2 Tindak Lanjut
Petugas Pengelola Airtanah harus memiliki kompetensi dan wawasan yang
memadai. Mengingat perkembangan kebijakan dan lingkungan strategis yang
sedemikian pesat, maka para penyelenggara airtanah harus terus menerus
meningkatkan pengetahuan dan keahlian/ keterampilannya, serta terus berkreasi/
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
62 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
berinovasi agar dapat menjawab tantangan dan kendala yang ada rangka
mendukung terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Air yang profesional.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 63
DAFTAR PUSTAKA
Andriyani S., Ramelan A, H., dan Sutarno., “Identifikasi Akuifer di Sekitar Kawasan Karst
Gombong Selatan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dengan Metode
Geolistrik Schlumberger”, Jurnal EKOSAINS, Vol II, No 1, 2010.
Maemuna S., Darsono., dan Legowo B., “Identifikasi Akuifer di Sekitar Kawasan Karst
Gombong Selatan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dengan Metode
Geolistrik Schlumberger”, Jurnal Fisika dan Aplikasinya, Vol 13 Nomor 2, 2017.
Murti, H, A., “Analisis Pendugaan Potensi Akuifer dengan Metode Geolistrik Resistivitas
Sounding dan Mapping di Kawasan Karst Kecamatan Giritontro Kabupaten
Wonogiri”, Laporan Tesis Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.
Prandika, R, P., “Laporan Praktikum Geofisika I”, Laboratorium Geofisika Universitas
Padjadjaran, Bandung, 2014.
SNI 2528, Tata Cara Pengukuran Geolistrik Wenner untuk Eksplorasi Air Tanah, Standar
Nasional Indonesia, 2012.
SNI 2818, Tata Cara Pengukuran Geolistrik Schlumberger untuk Eksplorasi Air Tanah,
Standar Nasional Indonesia, 2012.
SNI 7751, Tata Cara Pencatatan Akuifer dengan Metode logging Geolistrik Tahanan Jenis
Normal dan Log Normal dalam Rangka Eksplorasi Air Tanah, Standar Nasional
Indonesia, 2012.
Suyanto, I., “Perbandingan Survei dan Analisis Data Geolistrik Sounding Daerah Pantai dan
Pegunungan Studi Kasus Penyelidikan Air Tanah di Kabupaten Kendal, Jawa
Tengah”, Laboratorium FMIPA Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013
Subardjo., Nurdin H., Slamet S., dan Daromono S.,“Pengukuran Geolistrik Tahanan Jenis
untuk Pencarian Sumber Air Tanah Di Cipanas Jawa Barat”, Prosiding Seminar
Pranata Nuklir dan Teknisi Litkayasa, ISBN, 979-8769-10-4, Jakarta, 2000.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
64 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
GLOSARIUM
Elektrode
: Konduktor yang digunakan untuk bersentuhan dengan bagian atau
media non-logam dari sebuah sirkuit (misal semikonduktor,
elektrolit atau vakum).
Geolistrik
: Merupakan salah satu metode geofisika yang bertujuan
mengetahui sifat-sifat kelistrikan lapisan batuan dibawah
permukaan tanah dengan cara menginjeksikan arus listrik ke
dalam tanah.
Kalibrasi
: Kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai
penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara
membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur
(traceable) ke standar nasional maupun internasional untuk
satuan ukuran dan/ atau internasional dan bahan-bahan acuan
tersertifikasi.
Karst
: Sebuah bentuk permukaan bumi yang pada umumnya dicirikan
dengan adanya depresi tertutup (closed depression), drainase
permukaan, dan gua. Daerah ini dibentuk terutama oleh
pelarutan batuan, kebanyakan batu gamping.
Noise : Sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam suatu
sistem transmisi.
Resistivitas listrik : Salah satu metode geofisika yang menyelidiki struktur bawah
permukaan dengan menggunakan sifat - sifat kelistrikan batuan.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 65
KUNCI JAWABAN
A. Latihan Materi Pokok 1: Konfigurasi Sclumberger
1. Sebutkan prosedur pengisian tabel pengukuran!
Jawaban:
Keadaan geologi, satuan lapisan batuan dengan batas vertikal dan lateral, struktur
geologi, kondisi air tanah, penentuan lokasi, tanda tangan petugas.
2. Sebutkan kelemahan konfigurasi Schlumberger!
Jawaban:
Kelemahan dari konfigurasi Schlumberger ini adalah pembacaan tegangan pada
elektrode MN adalah lebih kecil terutama ketika jarak AB yang relatif jauh,
sehingga diperlukan alat ukur multimeter yang mempunyai karakteristik ‘high
impedance’ dengan akurasi tinggi yaitu yang bisa mendisplay tegangan minimal 4
digit atau 2 digit di belakang koma. Atau dengan cara lain diperlukan peralatan
pengirim arus yang mempunyai tegangan listrik DC yang sangat tinggi.
3. Sebutkan parameter yang diukur dan dihitung dalam konfigurasi Schlumberger!
Jawaban:
Parameter yang diukur :Jarak antara stasiun dengan elektrode-elektrode (AB/2
dan MN/2), Arus (I), Beda Potensial (∆ V) Parameter yang dihitung: Tahanan jenis
(R), Faktor geometrik (K), Tahanan jenis semu (ρ).
B. Evaluasi Materi Pokok 1: Konfigurasi Sclumberger
1. A
2. B
3. C
C. Latihan Materi Pokok 2: Konfigurasi Wenner
1. Sebutkan tiga langkah awal prosedur pengukuran!
Jawaban:
Pemodelan tidak langsung adalah penyesuaian lengkung lapangan dengan
lengkung baku sedangkan untuk pemodelan langsung pemodelan dengan
menggunakan software.
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
66 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
2. Sebutkan tiga perbedaan konfigurasi wenner dan konfigurasi schlumberger!
Jawaban:
Keunggulan dari konfigurasi Wenner ini adalah ketelitian pembacaan tegangan
pada elektrode MN lebih baik dengan angka yang relatif besar karena elektrode
MN yang relatif dekat dengan elektrode AB.
3. Sebutkan nilai tahan tanah untuk sedimen terkonsolidasi!
Jawaban:
10 sampai 100 ohm
D. Evaluasi Materi Pokok 2: Konfigurasi Wenner
1. A
2. B
3. C
E. Latihan Materi Pokok 3: Konfigurasi Pole Dipole
1. Sebutkan kelemahan konfigurasi pole dipole!
Jawaban:
Kelemahan dari konfigurasi pole-dipole adalah tingkat akurasi dari posisi benda
atau obyek yang kurang akurat dibandingkan konfigurasi dipole-dipole, hal ini
disebabkan oleh konfigurasi elektrode yang tidak simetris.
2. Sebutkan tiga peralatan konfigurasi pole dipole!
Jawaban:
GPS, Elektrode, dan Terameter ABEM 1000.
3. Sebutkan kedalaman investigasi pole dipole!
Jawaban:
Kurang dari 500m dibawah permukaan tanah.
F. Evaluasi Materi Pokok 3: Konfigurasi Pole Dipole
1. A
2. B
3. C
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI 67
G. Latihan Materi Pokok 4: Peralatan Survei
1. Sebutkan empat alat pengukuran survei!
Jawaban:
Resistivity meter nainura NRD 22, ABEM SAS 1000, MAE X612-EM, ARES GF
Instrument.
2. Sebutkan kelebihan alat survei SAS 300 C!
Jawaban:
a. Pengukuran dapat di upgrade melalui komputasi
b. Ringan dan portable (bertanya hanya 1 kg, tidak termasuk baterai)
c. 100 mA current source
d. Anti short circuit
e. Long life battery (hemat arus)
f. Bisa digunakan untuk pengukuran sounding atau profiling/ mapping
resistivitas
g. Bisa digunakan untuk pengukuran dalam skala laboratorium
3. Sebutkan standar aksesoris yang di gunakan untuk alat survei ARES!
Jawaban:
a. T-piece (untuk sambungan bagian kabel multi elekroda dan kabel untuk
elektrode)
b. Kabel untuk baterai eksternal 12 V
c. Kabel RS232C dan USB
H. Evaluasi Materi Pokok 4: Peralatan Survei
1. A
2. B
3. C
I. Latihan Materi Pokok 5: Penentuan Desain Survei Geolistrik
1. Sebutkan lima peralatan lapangan yang digunakan dalam pengambilan data!
Jawaban:
Kompas, kabel elektrode
MODUL 5 DESAIN SURVEI GEOLISTRIK UNTUK AIRTANAH
68 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
2. Apa konfigurasi yang cocok digunakan dalam kawasan karst?
Jawaban:
Metode geolistrik konfigurasi pole dipole dikarenakan elektrode arus C2 terletak
jauh diluar jalur rencana pengukuran.
3. Apa konfigurasi yang cocok digunakan dalam kawasan pantai?
Jawaban:
Konfigurasi Schlumberger
J. Evaluasi Materi Pokok 5: Penentuan Desain Survei Geolistrik
1. A
2. B
3. C