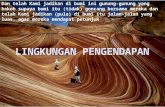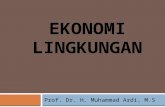MAKALAH BIOKIMIA LINGKUNGAN PERAIRAN
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of MAKALAH BIOKIMIA LINGKUNGAN PERAIRAN
MAKALAH BIOKIMIA
BIOKIMIA LINGKUNGAN PERAIRAN
( Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biokimia yang
dibimbing oleh DR. Yuni Kilawati , S.Pi, MS )
Oleh :
1.Suryanto ( 135080101111118 )
2.Aji Sanjaya ( 135080101111104 )
3.Dadang Kurniawan ( 135080101111105 )
4.Muhklas Shah Winarno ( 135080101111096 )
5.Ainun ( 135080101111107 )
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2014
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah
SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunianya, sehingga
kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian
mengenai Biokimia di dalam perairan bentuk makalah. Dalam
penyusunan laporan ini tidak sedikit hambatan yang penulis
hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam
penyusanan materi ini berkat bantuan, dorongan dan bimbingan
dari dosen pembimbing sehingga kendala-kendala yang penulis
hadapi dapat diatasi. Oleh karena itu, kamii mengucapkan
terima kasih kepada dosen bidang studi biokimia yang telah
memberikan tugas, petunjuk kepada kami sehingga kami
termotivasi untuk menyelesaikan laporan ini. Dan tak lupa pula
kami ucapkan banyak terimakasih kepada rekan-rekan yang
turut berpartisipasi dalam penyelesaian pembuatan laporan ini.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan
pemikiran bagi pihak yang membutuhkan. Untuk itu kritik dan
saran dari semua pihak sangat kami harapkan.
Daftar Isi
Kata pengantar................................i
Daftar isi...................................ii
Bab I: Pendahuluan............................1
1.1 Latar belakang.......................11.2 Tujuan dan Manfaat...................1
Bab II: Pembahasan............................2
2.1 Air..................................22.2 Pencemaram...........................3
2.2.1 Pencemaran air.................32.2.2 Hal umum penyebab pencemaranperairan.............................4
2.2.3 Limbah.........................42.2.4 Komponen limbah cair...........52.2.5 Indikator Pencemaran Perairan. .52.2.6 Kebutuhan Oksigen Biokimia.....92.2.7 Kebutuhan Oksigen Kimia.......102.2.8 Posfat........................102.2.9 Self Purification.............11
Bab III: Penutup…………………………………………………….........12
3.1 Kesimpulan…………………………………………….…12
3.2 Saran………………………………………………….…..12
Daftar Pustaka……………………………………………………….13
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Air merupakan komponen lingkungan yang penting bagi
kehidupan. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan
di bumi, sehingga tidak ada kehidupan seandainya di bumi tidak
ada air. Namun demikian, air dapat menjadi malapetaka bilamana
tidak tersedia dalam kondisi yang benar, baik kualitas maupun
kuantitasnya. Air yang relatif bersih sangat didambakan oleh
manusia, baik untuk keperluan hidup sehari-hari, untuk
keperluan industri, untuk kebersihan sanitasi kota, maupun
untuk keperluan pertanian dan lain sebagainya.
Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi
dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya
buruk akan mengakibatkan lingkungan hidup menjadi buruk
sehingga akan mempengaruhi kesehatan dan keselamatan manusia
serta mahluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan
menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung
dan daya tampung dari sumberdaya air yang pada akhirnya akan
menurunkan kekayaan sumberdaya alam. Untuk mendapat air yang
baik sesuai dengan standar tertentu, saat ini menjadi barang
yang mahal, karena air sudah banyak tercemar oleh bermacam-
macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia, sehingga
secara kualitas, sumberdaya air telah mengalami penurunan.
Demikian pula secara kuantitas, yang sudah tidak mampu
memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.
1.2 Rumusan Masalah1. Bagaimana pengertian dan penjelasan dari Air ?
2. Apa definisi dari pencemaran dan pencemaran Air ?
3. Apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran didalam
perairan
4. Bagaimana indikator dari pencemaran perairan ?
5. Bagamaina upaya untuk mengembalikan kondisi perairan
yang tercemar menjadi kondisi yang normal kembali ?
6. Apa saja molekul biokimia ( Biomolekul ) dalam
perairan?
1.3 Tujuan
Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu sebagai
berikut :
1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pengertian dan
penjelasan air
2. Untuk mengetahui dan memahami denifisi dari pencemaran
dan pencemaran air
3. Untuk mengetahui dan memahami penyebab terjadinya
pencemaran
4. Untuk mengetahui dan memahami indikator dari pencemaran
perairan
5. Untuk mengetahui dan memahami upaya untk mengembalikan
kondisi perairan tercemar menjadi kondisi yang normal
kembali.
6. Untuk mengetahui dan memahami molekul biokimia
( Biomolekul ) yang ada di dalam perairan.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Air
Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki
fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan
manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga
merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan
(Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2010).Air merupakan
salah satu senyawa kimia yang terdapat di alam secara
berlimpah-limpah akan tetapi ketersediaan air yang memenuhi
syarat bagi keperluan manusia relatif sedikit karena dibatasi
oleh berbagai faktor (Effendi,2003). Dari sekitar 1.386 juta
km3 air yang ada di bumi, sekitar 1.337 km3 (97,39%) berada di
samudera atau lautan dan hanya sekitar 35 juta km3 (25,53%)
berupa air tawar di daratan dan sisanya dalam bentuk gas/uap.
Jumlah air tawar tersebut sebagian besar (69%) berupa
gumpalan es dan glasier yang terperangkap di daerah kutub,
sekitar 30% berupa air tanah dan hanya sekitar 1% terdapat
dalam sungai, danau dan waduk (Suripin, 2002). Kuantitas air
di alam ini jumlahnya relatif tetap namun kualitasnya semakin
lama semakin menurun. Kuantitas/jumlah air umumnya dipengaruhi
oleh lingkungan fisik daerah seperti curah hujan, topografi
dan jenis batuan sedangkan kualitas air sangat dipengaruhi
oleh lingkungan sosial seperti kepadatan penduduk dan
kepadatan sosial (Hadi dan Purnomo, 1996 dalam Lutfi, 2006).
Air yang memadai bagi konsumsi manusia hanya 0,003% dari
seluruh air yang ada (Effendi, 2003).
Habitat air tawar menempati daerah yang relatif kecil
pada permukaan bumi dibandingkan habitat laut dan daratan
namun habitat ini mempunyai kepentingan bagi manusia yang jauh
lebih berarti karena habitat air tawar merupakan sumber air
yang praktis dan murah untuk berbagai keperluan, baik rumah
tangga, domestik, maupun industri. Selain itu ekosistem air
tawar menawarkan sistem pembuangan yang memadai dan paling
murah (Odum, 1996).
2.2 Pencemaran dan Pencemaran Air
2.2.1 Pencemaran
Pencemaranlingkungan adalah perubahan ligkungan yang
tidak menguntungkan sebagian karena tindakan-tindakan
manusia yang disebabkan oleh perubahan pola pembentukan
energi dan materi, tingkatan radiasi, bahan bahan fisika,
kimia dan jumlah organisme. Perubahan ini dapat
mempengaruhi manusia secara langsung atau tidak langsung
melalui hasil pertanian, peternakan, benda-benda,
perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas
(Fardiaz. 1992).
Menurut Hidayat (1981), pada dasarnya pencemaran
lingkungan dapat dibagi dalam tiga tingkatan yaitu : (1)
gangguan, merupakan bentuk pencemaran yang paling ringan,
(2) pencemaran temporer, berjangka pendek karena alam
mampu mencernakannya sehingga lingkungan dapat kembali
seperti semula, dan (3) pencemaran permanen, bersifat
tetap karena alam tidak mampu kembali mencernakannya
(dikenal sebagai perubahan sumberdaya alam). Pencemaran
lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009) adalah
masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi
dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan
hidup yang telah ditetapkan.
2.2.2 Pencemaran Air
Pencemaran adalah suatu penyimpangan dari keadaan no
rmalnya. Jadi pencemaran air adalah suatu keadaan air
tersebut telah mengalami penyimpangan dari keadaan
normalnya. Keadaan normal air masih tergantung pada
factor penentu, yaitu kegunaan air itu sendiri dan asal
sumber air (Wardhana, 2004). Cottam (1969) mengemukakan
bahwa pencemaran air adalah bertambahnya suatu material
atau bahan dan setiap tindakan manusia yang mempengaruhi
kondisi perairan sehingga mengurangi atau merusak daya
guna perairan. Industri pertambangan dan energi mempunyai
pengaruh besar terhadap perubahan lingkungan karena
mengubah sumber daya alam menjadi produk baru dan
menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan.(Darsono,
1992).
Kumar (1977) berpendapat bahwa air dapat tercemar ji
ka kualitas atau komposisinya baik secara langsung atau
tidak langsung berubah oleh aktivitas manusia sehingga
tidak lagi berfungsi sebagai air minum, keperluan rumah
tangga, pertanian, rekreasi atau maksud lain seperti
sebelum terkena pencemaran.
2.3 Penyebab Terjadinya Pencemaran di Dalam Perairan
Perkembangan penduduk dan kegiatan manusia telah
meningkatkansungai-sungai, terutama
sungai sungai yang melintasi daerah perkotaan dimana seba
gia air bekas kegiatan manusia dibuang ke system perairan
yang sedikit atau tanpa pengolahan sama sekali terlebih
dahulu. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas air sungai
(Darsono, 1992).
Penyebab pencemaran air berdasarkan sumbernya secara
umum dapat dikategorikan sebagai sumber kontaminan
langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi
effluent yang keluar dari industri, TPA (Tempat Pemrosesan
Akhir Sampah), dan sebagainya. Sumber tidak langsung
yaitu kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air
tanah, atau atmosfer berupa hujan. Tanah dan air tanah
mengandung mengandung sisa dari aktivitas pertanian
seperti pupuk dan pestisida. Kontaminan dari atmosfer
juga berasal dari aktivitas manusia yaitu pencemaran
udara yang menghasilkan hujan asam. Penyebab pencemaran
air dapat juga digolongkan berdasarkan aktivitas manusia
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu limbah yang
berasal dari industri, rumah tangga, dan pertanian
(Suriawiria, 1996).
2.3.1 Limbah
Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu
proses produksi baik industri maupun domestik (rumah
tangga). Limbah yang dihasilkan berupa sampah, air kakus
(black water), dan air buangan dari berbagai aktivitas
domestic lainnya (grey water). Menurut Undang-undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Kementerian Negara Lingkungan Hidup,
2009),
limbah didefinisikan sebagai sisa suatu usaha dan/atau
kegiatan. Limbah cair adalah air yang membawa sampah
(limbah) dari rumah, bisnis dan industri. Limbah adalah
sampah cair dari suatu lingkungan masyarakat dan terutama
terdiri dari air yang telah dipergunakan dengan hampir
0,1% dari padanya berupa benda-benda padat yang terdiri
dari zat organik dan an-organik. Pelimbahan akan berbeda
kekuatan dan komposisinya dari suatu kota ke kota yang
lain disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang nyata dalam
kebiasaankebiasaan masyarakat yang berbeda-beda, sifat
makanan dan pemakaian air perkapita. Tidak ada dua jenis
sampah yang benar-benar sama. Pelimbahan pada kota-kota
non industri, kebanyakan terdiri dari sampah domestik
yang murni (Mahida, 1986). Limbah padat lebih dikenal
sebagai sampah, yang seringkali tidak dikehendaki
kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila
ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan
kimia senyawa organik dan senyawa anorganik. Dengan
konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah
dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi
kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan
terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang
ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan
karakteristik limbah.
2.3.2 Komponen Limbah Cair
Komponen limbah cair (Tchobanoglous and Eliassen
dalam Soeparman, 2001) antara lain limbah cair domestik
(domestic waste water), limbah cair industri (industrial waste
water), rembesan dan luapan (infiltration and inflow). Limbah
cair domestik adalah hasil buangan dari perumahan,
bangunan, perdagangan, perkantoran dan sarana sejenisnya.
Limbah cair domestic mengandung susunan senyawa organik,
baik itu alami maupun sintetis. Senyawa ini masuk ke
dalam badan air sebagai hasil dari aktivitas manusia.
Penyusun utamanya berupa polysakarida (karbohidrat),
polipeptida (protein), lemak (fats) dan asam nukleat (nucleic
acid).
2.4 Indikator Pencemaran Perairan
Beberapa karakteristik atau indikator kualitas air
yang disarankan untuk dianalisis sehubungan pemanfaatan
sumberdaya air untuk berbagai keperluan, antara lain
parameter fisika, kimia dan biologi (Effendi, 2003).
Indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar
adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati
yang dapat digolongkan menjadi :
- Pengamatan secara fisik, yaitu pengamatan pencemaran
air berdasarkan tingkat kejernihan air (kekeruhan),
perubahan suhu, warna dan adanya Perubahan warna baud an
rasa.
- Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran
air berdasarkan zat kimia yang
terlarut dan perubahan pH.
- Pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran
air berdasarkan mikroorganisme yang ada dalam air,
terutama ada tidaknya bakteri patogen. Indikator yang
umum digunakan pada pemeriksaan pencemaran air adalah pH
atau konsentrasi ion hydrogen, oksigen terlarut (Dissolved
Oxygen, DO), kebutuhan oksigen biokimia (Biochemical Oxygen
Demand, BOD) serta kebutuhan oksigen kimiawi (Chemical Oxygen
Demand, COD).
Pemantauan kualitas air pada sungai perlu disertai
dengan pengukuran dan pencatatan debit air agar analisis
hubungan parameter pencemaran air dan debit badan air
sungai dapat dikaji untuk keperluan pengendalian
pencemarannya (Irianto dan Machbub, 2003).
- Parameter Fisika
a. Suhu
Suhu sangat berpengaruh terhadap proses-proses yang
terjadi dalam badan air. Suhu air buangan kebanyakan
lebih tinggi daripada suhu badan air. Hal ini erat
hubungannya dengan proses biodegradasi. Pengamatan suhu
dimaksudkan untuk mengetahui kondisi perairan dan
interaksi antara suhu dengan aspek kesehatan habitat dan
biota air lainnya. Kenaikan suhu air akan menimbulkan
beberapa akibat sebagai berikut : (1) jumlah oksigen
terlarut di dalam air menurun. (2) kecepatan reaksi kimia
meningkat. (3) kehidupan ikan dan hewan air lainnya
terganggu.(4) jika batas suhu yang mematikan terlampaui,
ikan dan hewan air lainnya akan mati. (Fardiaz, 1992)
b. Daya Hantar Listrik
Daya hantar listrik adalah bilangan yang menyatakan
kemampuan larutan cair untuk menghantarkan arus listrik.
Kemampuan ini tergantung keberadaan ion, total
konsentrasi ion, valensi konsentrasi relatif ion dan suhu
saat pengukuran. Makin tinggi konduktivitas dalam air,
air akan terasa payau sampai asin. (Mahida, 1986).
c. Total Padatan Tersuspensi (Total Suspended Solid, TSS) dan
Total Padatan Terlarut (Total Dissolved Solid, TDS)
Sugiharto (1987) mendefinisikan sebagai jumlah berat
dalam air limbah setelah mengalami penyaringan dengan
membran berukuran 0,45 mikro. Total padatan tersuspensi
terdiri atas lumpur dan pasir halus serta jasad-jasad
renik terutama yang disebabkan oleh kikisan tanah atau
erosi yang terbawa ke dalam badan air. Masuknya padatan
tersuspensi ke dalam perairan dapat menimbulkan kekeruhan
air. Hal ini menyebabkan menurunnya laju fotosintesis
fitoplankton, sehingga produktivitas primer perairan
menurun, yang pada gilirannya menyebabkan terganggunya
keseluruhan rantai makanan. Padatan tersuspensi yang
tinggi akan mempengaruhi biota di perairan melalui dua
cara. Pertama, menghalangi dan mengurangi penentrasi
cahaya ke dalam badan air, sehingga mengahambat proses
fotosintesis oleh fitoplankton dan tumbuhan air lainnya.
Kedua, secara langsung TDS yang tinggi dapat mengganggu
biota perairan seperti ikan karena tersaring oleh insang.
Menurut Fardiaz (1992), padatan tersuspensi akan
mengurangi penetrasi cahaya ke dalam air. Penentuan
padatan tersuspensi sangat berguna dalam analisis
perairan tercemar dan buangan serta dapat digunakan untuk
mengevaluasi kekuatan air,buangan domestik, maupun
menentukan efisiensi unit pengolahan.Padatan tersuspensi
mempengaruhi kekeruhan dan kecerahan air. Oleh karena itu
pengendapan dan pembusukan bahan-bahan organik dapat
mengurangi nilai guna perairan. Total padatan terlarut
merupakan bahan-bahan terlarut dalam air yang tidak
tersaring dengan kertas saring millipore dengan ukuran pori
0,45 μm. Padatan ini terdiri dari senyawa-senyawa
anorganik dan organik yang terlarut dalam air, mineral
dan garam-garamnya. Penyebab utama terjadinya TDS adalah
bahan anorganik berupa ion-ion yang umum dijumpai di
perairan. Sebagai contoh air buangan sering mengandung
molekul sabun, deterjen dan surfaktan yang larut air,
misalnya pada air buangan rumah tangga dan industri
pencucian.
d. Kekeruhan dan Kecerahan
Mahida (1986) mendefinisikan kekeruhan sebagai
intensitas kegelapan di dalam air yang disebabkan oleh
bahan-bahan yang melayang. Kekeruhan perairan umumnya
disebabkan oleh adanya partikel-partikel suspensi seperti
tanah liat, lumpur, bahan-bahan organik terlarut,
bakteri, plankton dan organisme lainnya. Effendi (2003),
menyatakan bahwa tingginya nilai kekeruhan juga dapat
menyulitkan usaha penyaringan dan mengurangi efektivitas
desinfeksi pada proses penjernihan air.
- Parameter Kimia
a. Derajat Keasaman (pH)
Derajat keasaman merupakan gambaran jumlah atau
aktivitas ion hydrogen dalam perairan. Secara umum nilai
pH menggambarkan seberapa besar tingkat keasaman atau
kebasaan suatu perairan. Perairan dengan nilai pH = 7
adalah netral, pH < 7 dikatakan kondisi perairan bersifat
asam, sedangkan pH > 7 dikatakan kondisi perairan
bersifat basa (Effendi, 2003). Adanya karbonat,
bikarbonat dan hidroksida akan menaikkan kebasaan air,
sementara adanya asamasam mineral bebas dan asam karbonat
menaikkan keasaman suatu perairan. Sejalan dengan
pernyataan tersebut, Mahida (1986) menyatakan bahwa
limbah buangan industri dan rumah tangga dapat
mempengaruhi nilai pH perairan. Nilai pH dapat
mempengaruhi spesiasi senyawa kimia dan toksisitas dari
unsur-unsur renik yang terdapat di perairan, sebagai
contoh H2S yang bersifat toksik banyak ditemui di
perairan tercemar dan perairan dengan nilai pH rendah.
b. Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen, DO)
Oksigen terlarut adalah gas oksigen yang terdapat di
perairan dalam bentuk molekul oksigen bukan dalam bentuk
molekul hidrogenoksida, biasanya dinyatakan dalam mg/l
(ppm) (Darsono, 1992). Oksigen bebas dalam air dapat
berkurang bila dalam air dalam terdapat kotoran/limbah
organik yang degradable. Dalam air yang kotor selalu
terdapat bakteri, baik yang aerob maupun yang anaerob.
Bakteri ini akan menguraikan zat organik dalam air
menjadi persenyawaan yang tidak berbahaya. Misalnya
nitrogen diubah menjadi persenyawaan nitrat, belerang
diubah menjadi persenyawaan sulfat. Bila oksigen bebas
dalam air habis/sangat berkurang jumlahnya maka yang
bekerja, tumbuh dan berkembang adalah bakteri anaerob
(Darsono, 1992).
Oksigen larut dalam air dan tidak bereaksi dengan
air secara kimiawi. Pada tekanan tertentu, kelarutan
oksigen dalam air dipengaruhi oleh suhu. Faktor lain yang
mempengaruhi kelarutan oksigen adalah pergolakan dan luas
permukaan air terbuka bagi atmosfer (Mahida, 1986).
Persentase oksigen di sekeliling perairan dipengaruhi
oleh suhu perairan, salinitas perairan, ketinggian tempat
dan plankton yang terdapat di perairan (di udara yang
panas, oksigen terlarut akan turun). Daya larut oksigen
lebih rendah dalam air laut jika dibandingkan dengan daya
larutnya dalam air tawar. Daya larut O2 dalam air limbah
kurang dari 95% dibandingkan dengan daya larut dalam air
tawar (Setiaji,1995) Terbatasnya kelarutan oksigen dalam
air menyebabkan kemampuan air untuk membersihkan dirinya
juga terbatas, sehingga diperlukan pengolahan air limbah
untuk mengurangi bahan-bahan penyebab pencemaran.
Oksidasi biologis meningkat bersama meningkatnya suhu
perairan sehingga kebutuhan oksigen terlarut juga
meningkat (Mahida, 1986). Ibrahim (1982) menyatakan bahwa
kelarutan oksigen di perairan bervariasi antara 7-14 ppm.
Kadar oksigen terlarut dalam air pada sore hari > 20 ppm.
Besarnya kadar oksigen di dalam air tergantung juga pada
aktivitas fotosintesis organisme di dalam air. Semakin
banyak bakteri di dalam air akan mengurangi jumlah
oksigen di dalam air. Kadar oksigen terlarut di alam
umumnya < 2 ppm. Kalau kadar DO dalam air tinggi maka
akan mengakibatkan instalasi menjadi berkarat, oleh
karena itu diusahakan kadar oksigen terlarutnya 0 ppm
yaitu melalui pemanasan (Setiaji, 1995)
2.4.1 Kebutuhan Oksigen Biokimia (Biochemical Oxygen Demand,
BOD5)
Biochemical Oxygen Demand merupakan ukuran jumlah zat
organik yang dapat dioksidasi oleh bakteri aerob/jumlah
oksigen yang digunakan untuk mengoksidasi sejumlah
tertentu zat organik dalam keadaan aerob. BOD5 merupakan
salah satu indikator pencemaran organik pada suatu
perairan. Perairan dengan nilai BOD5 tinggi
mengindikasikan bahwa air tersebut tercemar oleh bahan
organik. Bahan organik akan distabilkan secara biologik
dengan melibatkan mikroba melalui sistem oksidasi aerobik
dan anaerobik. Oksidasi aerobik dapat menyebabkan penurunan
kandungan oksigen terlarut di perairan sampai pada
tingkat terendah, sehingga kondisi perairan menjadi
anaerobik yang dapat mengakibatkan kematian organisme
akuatik.
Menurut Mahida (1981) BOD akan semakin tinggi jika
derajat pengotoran limbah semakin besar. BOD merupakan
indikator pencemaran penting untuk menentukan kekuatan
atau daya cemar air limbah, sampah industri, atau air
yang telah tercemar. BOD biasanya dihitung dalam 5 hari
pada suhu 200C. Nilai BOD yang tinggi dapat menyebabkan
penurunan oksigen terlarut tetapi syarat BOD air limbah
yang diperbolehkan dalam suatu perairan di Indonesia
adalah sebesar 30 ppm.
Kristianto (2002) menyatakan bahwa uji BOD mempunyai
beberapa kelemahan di antaranya adalah: (1) dalam uji BOD
ikut terhitung oksigen yang dikonsumsi oleh bahan-bahan
organik atau bahan-bahan tereduksi lainnya, yang disebut
juga Intermediate Oxygen Demand, (2) uji BOD membutuhkan
waktu yang cukup lama, yaitu lima hari (3) uji BOD yang
dilakukan selama lima hari masih belum dapat menunjukkan
nilai total BOD, melainkan ± 68 % dari total BOD, (4) uji
BOD tergantung dari adanya senyawa penghambat di dalam
air tersebut, misalnya germisida seperti klorin yang
dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang
dibutuhkan untuk merombak bahan organik, sehingga hasil
uji BOD kurang teliti.
2.4.2 Kebutuhan Oksigen Kimia (Chemical Oxygen Demand, COD)
Effendi (2003) menggambarkan COD sebagai jumlah
total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan
organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi
secara biologi maupun yang sukar didegradasi menjadi CO2
dan H2O. Berdasarkan kemampuan oksidasi, penentuan nilai
COD dianggap paling baik dalam menggambarkan keberadaan
bahan organik, baik yang dapat didekomposisi secara
biologis maupun yang tidak. Uji ini disebut dengan uji
COD, yaitu suatu uji yang menentukan jumlah oksigen yang
dibutuhkan oleh bahan oksidan misalnya kalium dikromat,
untuk mengoksidasi bahan-bahan organik yang terdapat di
dalam air. Banyak zat organik yang tidak mengalami
penguraian biologis secara cepat berdasarkan pengujian
BOD lima hari, tetapi senyawa-senyawa organic tersebut
juga menurunkan kualitas air. Bakteri dapat mengoksidasi
zat organic menjadi CO2 dan H2O. Kalium dikromat dapat
mengoksidasi lebih banyak lagi, sehingga menghasilkan
nilal COD yang lebih tinggi dari BOD untuk air yang sama.
Di samping itu bahan-bahan yang stabil terhadap reaksi
biologi dan mikroorganisme dapat ikut teroksidasi dalam
uji COD. Sembilan puluh enam persen hasil uji COD yang
selama 10 menit, kira-kira akan setara dengan hasil uji
BOD selama lima hari (Kristianto, 2002).
2.4.3 Posfat(PO4)
Keberadaan fosfor dalam perairan adalah sangat
penting terutama berfungsi dalam pembentukan protein dan
metabolisme bagi organisme. Fosfor juga berguna di dalam
transfer energi di dalam sel misalnya adenosine trifosfate
(ATP) dan adenosine difosfate (ADP) (Boyd, 1982) Menurut Peavy
et al. (1986), fosfat berasal dari deterjen dalam limbah
cair dan pestisida serta insektisida dari lahan
pertanian.
Fosfat terdapat dalam air alam atau air limbah
sebagai senyawa ortofosfat, polifosfat dan fosfat
organis. Setiap senyawa fosfat tersebut terdapat dalam
bentuk terlarut, tersuspensi atau terikat di dalam sel
organisme dalam air. Di daerah pertanian ortofosfat berasal
dari bahan pupuk yang masuk ke dalam sungai melalui
drainase dan aliran air hujan. Polifosfat dapat memasuki
sungai melaui air buangan penduduk dan industri yang
menggunakan bahan detergen yang mengandung fosfat,
seperti industry pencucian, industri logam dan
sebagainya. Fosfat organis terdapat dalam air buangan
penduduk (tinja) dan sisa makanan. Menurut Boyd (1982),
kadar fosfat (PO4) yang diperkenankan dalam air minum
adalah 0,2 ppm. Kadar fosfat dalam perairan alami umumnya
berkisar antara 0,005-0,02 ppm. Kadar fosfat melebihi 0,1
ppm, tergolong perairan yang eutrof.
2.5 Self PurificationLingkungan perairan bereaksi terhadap masuknya bahan
pencemar sebagai mekanisme alami untuk kembali pada
kualitas air semula.proses ini disebut Self purification yang
sebenarnya terdiri dari daur ulang material (Vismara,1998
Dalam Vagnetti,2003) definisi lain dari self purification
adalah pemulihan secara alami baik secara total ataupun
sebagian kembali ke kondisi awal dari bahan asing yang
secara kualitas ataupun kuantitas menyebabkan perubahan
karakteristik fisik,kimia dan atau Biologi yang terukur
di dalam air tersebut (Benoit,1971 Dalam
Vagnetti,2003).proses pemulihan secara alami berlangsung
secara fisik,kimiawi dan biologi yang secara signifikan
dapat mendukung alami proses pemurnian diri dan
menyebabkan kualitas air menjadi lebih baik dari kondisi
air semula (Vagnetti,2003).
2.6 Molekul Biokimia ( Biomolekul ) di Dalam Perairan
Ada 4 kelas molekul utama dalam biokimiayaitu: karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat.Banyak molekul biologi merupakan "polimer": dalam kasusini, monomer adalah mikromolekul yang relatif kecil yangbergabung menjadi satu untuk membentuk makromolekul-makromolekul, yang kemudian disebut sebagai "polimer".Ketika banyak monomer bergabung untuk mensintesissebuah polimer biologis, mereka melalui proses/tahap yangdisebut dengan sintesis dehidrasi.
a. KarbohidratKarbohidrat tersusun dari monomer yang disebut
sebagai monosakarida. Contoh dari monosakarida adalah glukosa (C6H12O6), fruktosa(C6H12O6), dan deoksiribosa (C5H10O4). Ketika 2 monosakarida melalui proses sintesis dehidrasi, maka air akan terbentuk, karena 2 atomhidrogen dan satu atom oksigen telepas dari 2 gugus hidroksil monosakarida.
b. Lipid.Lipid biasanya terbentuk dari satu
molekul gliserol yang bergabung dengan molekul lain. Di trigliserida, ada satu mol gliserol dan tiga molekul asam lemak. Asam lemak merupakan monomer disini.
Lipid, terutama fosfolipid, juga digunakan di beberapa produk obat-obatan, misalnya sebagai bahan pelarut (contohnya di infusparenteral) atau sebagai komponen pembawa obat (contohnya di liposom atau transfersom).
c. Protein.Protein merupakan molekul yang sangat besar-atau
makrobiopolimer- yang tersusun dari monomer yang disebutasam amino. Ada 20 asam amino standar, yang masing-masing terdiri dari sebuah gugus karboksil, sebuah gugus amino, dan rantai samping(disebut sebagai
grup "R"). Grup "R" ini yang menjadikan setiap asam aminoberbeda, dan ciri-ciri dari rantai samping ini akan berpengaruh keseluruhan terhadap suatu protein. Ketika asam amino bergabung, mereka membentuk ikatan khusus yangdisebut ikatan peptida melalui sintesis dehidrasi, dan menjadi Polipeptida, atau protein.
d. Asam Nukleat.Asam nukleat adalah molekul yang membentuk DNA,
substansi yang sangat penting yang digunakan oleh semua organisme seluler untuk menyimpan informasi genetik. Jenis asam nukleat yang paling umum adalahasam deoksiribosa nukleat dan asam ribonukleat. Monomernya disebut nukleotida. Nukleotida yang paling umum diantaranya Adenin, Sitosin, Guanin, Timin, dan Urasil. Adenin berpasangan dengan timin dan urasil, timin hanya berpasangan dengan adenin; sitosin dan guanin hanya dapatberpasangan satu sama lain.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki
fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan
manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum,
sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama
pembangunan.
2. Air dapat tercemar jika kualitas atau komposisinya baik s
ecara langsung atau tidak langsung berubah oleh aktivitas
manusia sehingga tidak lagi berfungsi sebagai air minum,
keperluan rumah tangga, pertanian, rekreasi atau maksud
lain seperti sebelum terkena pencemaran.
3. Penyebab pencemaran air berdasarkan sumbernya secara umum
dapat dikategorikan sebagai sumber kontaminan langsung
dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi effluent yang
keluar dari industri, TPA (Tempat Pemrosesan Akhir
Sampah), dan sebagainya. Sumber tidak langsung yaitu
kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah,
atau atmosfer berupa hujan.
4. Self purification adalah pemulihan secara alami baik
secara total ataupun sebagian kembali ke kondisi awal
dari bahan asing yang secara kualitas ataupun kuantitas
menyebabkan perubahan karakteristik fisik,kimia dan atau
Biologi yang terukur di dalam air tersebut
3.2 Saran
Bagi kita dan generasi akan datang sudah sepatutnya untuk
menjaga dan melindungi lingkungan perairan di Negara Indonesia
ini terutama dari pencemaran lingkungan dan pencemaran di
dalam perairan.
DAFTAR PUSTAKA
Cottam, T. 1969. Research for Establishment of Water Quality Criteria for
Aquatic Life. Reprint Transac of the 2nd Seminar on
Biology, April 20-24,
Ohio.
Darsono, V. 1992. Pengantar Ilmu Lingkungan. Penerbit
Universitas Atmajaya,
Yogyakarta, hal : 66, 68.
Effendi, H. 2003. Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan
Lingkungan Perairan. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
Fardiaz, S. 1992. Polusi Air dan Udara, Penerbit Kanisius,
Yogyakarta. Hal : 21-
23, 185
Hidayat, I. 1981. Water Pollution Control, Pengawasan Kualitas dan
Pencemaran Air, Paket Ilmu Jurusan Farmasi, FMIPA, ITB, BPC,
I.S.F.I,
Jawa Barat. Hal : 12-14
Irianto, E.W dan B. Machbub, 2003. Fenomena Hubungan Debit Air dan
Kadar
Zat Pencemar dalam Air Sungai (Studi Kasus : Sub DAS Citaru Hulu). JLP.
Vol 17 (52) Tahun 2005. Hal : 1-4.Diakses pada tanggal 4
Mei 2011 pkl : 00
: 31
Kristianto, P. 2002. Ekologi Industri. Penerbit ANDI. Yogyakarta
Kumar, H.D. 1977. Modern Concept of Ecology. Vikas Published Houses,
VT.
Ltd, New Delhi.
Lutfi A S. 2006. Kontribusi Air Limbah Domestik Penduduk di sekitar Sungai
TUK Terhadap Kualitas Air Sungai Kaligarang serta Upaya
Penangaannnya (Studi Kasus Kelurahan Sampangan dan Bendan
Ngisor
Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang).
Mahida, U.N. 1986. Pencemaran dan Pemanfaatan Limbah Industri.
Rajawali
Press, Jakarta.
Odum, E. P. 1996. Dasar – Dasar Ekologi. Terjemahan Samingan T.
Gadjah
Mada University Press. Yogyakarta
Setiaji, B. 1995. Baku Mutu Limbah Cair untuk Parameter Fisika, Kimia pada
Kegiatan MIGAS dan Panas Bumi. Lokakarya Kajian Ilmiah tentang
Komponen, Parameter, Baku Mutu Lingkungan dalam Kegiatan Migas dan
Panas Bumi, PPLH UGM, Yogyakarta.
Soeparman, H.M. 2001. Pembuangan Tinja dan Limbah Cair, suatu
pengantar.
Penerbit Buku Kedokteran (EGC)
Sugiharto. 1987. Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah. UI Press.
Jakarta.
Suripin. 2002. Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air. Penerbit Andi.
Yogyakarta.
Suriawiria, U. 1996. Air dalam Kehidupan dan Lingkungan yang Sehat.
Penerbit
Alumni. Bandung.
Wardhana, W.A, 2004. Dampak Pencemaran Lingkungan, Penerbit Andi,
Yogyakarta