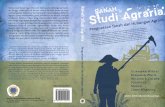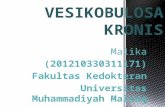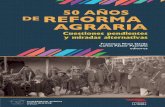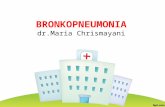HUKUM AGRARIA FIX
Transcript of HUKUM AGRARIA FIX
HUKUM AGRARIA
KONSOLIDASITANAH
1. ASMAUL HUSNA (120200221)
2. LINO .F.SIBARANI (120200223)
3. NOVICA.A.P (120200475)4. REGINA A.L.TOBING
(120200236)5. ROMAULI PURBA
(120200215)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2013
BAB IPENDAHULUAN
Tanah sebagai salah satu kekayaan bangsa Indonesia harusdimanfaatkan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Untukmewujudkan hal itu maka pemanfaatan tanah perlu dilaksanakandalam bentuk pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah. Modelyang dapat digunakan adalah konsolidasi tanah sebagai salah satuupaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah sertamenyelaraskan kepentingan individu dengan fungsi sosial tanahdalam rangka pelaksanaan pembangunan.
Dewasa ini pembangunan wilayah pemukiman di kawasanperkotaan berkembang dengan pesat. Oleh karena itu diperlukanpenguasaan dan pemanfaatan tanah secara optimal melaluipeningkatan efisiensi dan produktivitas pengunaan tanah, demiterwujudnya suatu tatanan penguasaan dan pengunaan yang tertibdan teratur.
Optimalisasi penguasaan dan pemanfaatan tanah dimaksuddilandasi dengan suatu keyakinan kebahagiaan hidup akan terwujudapabila didasarkan atas keserasian, keselarasan dan keseimbanganhidup manusia sebagai pribadi, dan terjalinnya hubungan antaramanusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan alam danhubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan tersebutmerupakan landasan ideal dan moral dalam pelaksanaan konsolidasitanah.
Selain landasan ideal dan moral tersebut, maka konsolidasitanah sebagai salah satu manifestasi pelaksanaan pembangunandidasarkan pula pada landasan konstitusional yakni pada pasal 33ayat 3 UUD 1945 dan landasan operasional yakni TAP MPR NO.IV/MPR/1999 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara yangmenghendaki agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat
dengan memperhatikan keseimbangan antara kemakmuran lahiriah dankepuasan batiniah. Oleh karena itu dikembangkan kebijaksanaanpertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengunaan tanahsecara adil, transparan , dan produktif dengan mengutamakan hak –hak rakyat setempat termasuk hak ulayat dan masyarakat adat,serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.
Dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan seyogianyamengacu pada Rencana Tata Ruang Kota dari suatu perencanaan kotayang sudah dibuat dengan baik dan memenuhi persyaratan formalyang melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan pelaksanaan konsolidasitanah perkotaan.
Hal – hal yang dikemukakan di atas merupakan manifestasiperlindungan hak – hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam UUD1945, Tap MPR No. XVII/ MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia, UUNo. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agrariaatau disebut Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) , UU No. 24 tahun1992 tentang Penataan Ruang , UU No.23 tahun 1997 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM,dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 tahun1991tentang Konsolidasi Tanah.
Konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan pertanahan mengenaipenataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usahapengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkankualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam denganmelibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan konsolidasitanah pada hakekatnya meliputi aspek – aspek antara lain :
a. Aspek pengaturan penguasaan atas tanah, tidak saja menatadan menertibkan bentuk fisik bidang – bidang tanah, tetapijuga hubungan hukum antara pemilik dan tanahnya.
b. Aspek penyerasian pengunaan tanah dengan rencana tata gunatanah atau tata ruang .
c. Aspek penyediaan yanah untuk kepentingan pembangunan jalandan fasilitas umum lainnya yang diperlukan.
d. Aspek peningkatan kualitas lingkungan hidup atau konservasisumber daya alam.
Dalam kegiatan konsolidasi tanah sebagai bagian programpembangunan akan dihindarkan kegiatan penggusuran terhadapmasyarakat yang menjadi peserta.
Pengaturan hukum konsolidasi tanah saat ini belum memadaidijadikan sebagai instrument kebijakan pertanahan dalam penataanruang. Hal ini karena peraturan perundang – undangan mengenaikonsolidasi tanah yang masih pada tingkat Peraturan Kepala Badanmempunyai beberapa kelemahan. Salah satu diantaranya adalahperaturan tersebut belum mampu mengikat para pihak untukmelaksanakan konsolidasi tanah. Peraturan yang ada saat ini hanyabersifat intern – administratif bagi aparat pertanahan untukmelaksanakan konsolidasi tanah.
Pelaksanaan konsolidasi tanah didasarkan pada perjanjianantara pihak peserta konsolidasi tanah dengan pelaksana, yaknikantor pertanahan melalui penandatanganan surat persetujuanpelaksanaan konsolidasi tanah dan surat pelepasan ha katas tanah.Akibat hukum dari kesepakatan tersebut adalah timbulnya hak dankewajiban masing – masing pihak. Kewajiban peserta konsolidasitanah adalah menyetujui pelaksanaan konsolidasi tanah danmemberikan sumbangan tanah untuk pembangunan. Kewajiban pelaksanakonsolidasi tanah adalah melaksanakan konsolidasi tanah, yaknimelakukan penataan bidang – bidang tanah menjadi tertib danteratur. Namun dalam perautan perundang – undangan mengenaikonsolidasi tanah belum diatur mengenai hak dan kewajiban masing– masing pihak secara rinci.
BAB II
PERMASALAHANBerlandaskan pada pasal 1 ayat (3) UUD’45 Indonesia merupakanNegara hukum , sehingga segala tindakan, kebijakan, kegiatanpemerintah yang menyangkut kepentingan umun harus ada dasarnya .Konsolidasi Tanah adalah salah satu kebijakan Pemerintah dibidangpertanahan, yang juga harus mempunyai dasar hukum gunapelaksanaannya dalam masyarakat.
Kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebagian besarwarga Indonesia kehidupannya bergantung kepada tanah dan sumberdaya alam. Sudah seharusnya pemerintah menjadikan masalahpertahanan dan kekayaan alam, sebagai salah satu isu strategisyang di prioritaskan penataannya. Pemerintah hendaknyamemprioritaskan perlindungan dan penataan hak-hak masyarakat atastanah dan kekayaan alam selama ini diabaikan.
Dengan demikian dalam makalah ini kami mengangkat beberapapermasalahan agar cakupan dari pokok bahasan tidak terlalu luasdan keluar dari jalur pembahasan.
Dalam hal ini kami mengangkat beberapa permasalahan , antara lain:
1. Apa landasan hukum pelaksanaan konsolidasi tanah?
2. Bagaimana kompleksitas dari penataan ruang kota?
BAB III
PEMBAHASAN
Tanah adalah kekayaan bangsa Indonesia yang harus
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat, seperti yang telah
tercantum dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam proses
pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat tersebut perlu
dilaksanakan sebuah pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah
dan hasil guna penggunaan tanah serta menyelaraskan kepentingan
individu dengan fungsi social tanah dalam rangka pelaksanaan
pembangunan dan juga meningkatkan peran serta aktif para pemilik
tanah dalam pembangunan dan upaya pemerataan hasil-hasilnya perlu
dilaksanakan Konsolidasi Tanah baik di perkotaan maupun di
perdesaan. Perkembangan kawasan perkotaan berlangsung sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi yang kemudian mendorong pertumbuhan
berbagai aktivitas terkait termasuk bidang permukiman. Di satu
sisi terjadi peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi yang
menyebabkan pertambahan permintaan tanah untuk permukiman dan
perumahan beserta fasilitas umum lainnya, sementara di sisi lain
penyediaan tanah tidak mengalami pertambahan. Hal ini menjadi
salah satu penyebab tidak terkendalinya penggunaan tanah dan
tidak memadainya infrastruktur yang mendukung suatu kota sehingga
kota tidak menjadi suatu kawasan yang nyaman bagi penduduknya.
Banyaknya kepentingan komponen dan kompleksnya pemanfaatan
ruang di kawasan perkotaan menambah rumitnya permasalahan
penataan ruang di kawasan perkotaan. Berkaitan dengan masalah
tersebut, dibutuhkan suatu mekanisme perencanaan kawasan
perkotaan dan pelaksanaannya yang dapat berjalan selaras dengan
perkembangan dan pertumbuhan suatu kota. Konsolidasi tanah,
mengupayakan penataan kembali penguasaan, pemilikan dan
penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah serta
mengupayakan pengadaan tanah untuk pembangunan yang meningkatkan
kualitas lingkungan hidup dan pemeliharaan sumber daya alam,
dapat menjadi salah satu sarana pembangunan kawasan perkotaan.
Konsep yang memadukan aspek legalitas penguasaan tanah dan aspek
fisik penggunaan tanah ini, yang melibatkan masyarakat secara
langsung dalam pelaksanaannya, diharapkan dapat mengurangi
masalah pertumbuhan kota yang tidak terkendali. Di samping itu,
konsolidasi tanah dapat pula menjadi instrumen yang efektif dalam
pelaksanaan penataan ruang kawasan perkotaan, salah satunya dalam
menjalankan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang.
Berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi
daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menggunakan
konsolidasi tanah sebagai salah satu sarana dalam pembangunan
kawasan perkotaannya. Daerah diharapkan dapat memetik manfaat
dari penerapan konsolidasi tanah ini yaitu berupa kawasan
perkotaan yang teratur, tertib dan sehat dengan didukung sarana
dan prasarana yang menunjang kawasan tersebut dengan selalu
memperhatikan tata ruang wilayah dan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaannya.
Dalam diktum Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor
4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah dinyatakan bahwa tanah
sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dimanfaatkan untuk
sebesar – besar kemakmuran rakyat.
Untuk mencapai pemanfaatan tersebut, perlu dilakukan
konsolidasi tanah sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna dan
hasil guna penggunaan tanah serta menyelaraskan kepentingan
individu dengan fungsi sosial tanah dalam rangka pelaksanaan
pembangunan1.
Secara yuridis, pengertian konsolidasi tanah adalah
kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan
tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk
meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan
melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
H.Idham mengemukakan dari dari pengertian yuridis diatas dapat
diidentifikasikan beberapa elemen substansial dari konsolidasi
tanah, yaitu
1. konsolidasi tanah merupakan kebijakan pertanahan;
1 Supriadi SH.M.Hum. hukum agraria. Sinar grafika,2009.hal.263
2. pengadaan tanah;
3. konsolidasi tanah bertujuan untuk kepentingan pembangunan,
meningkatkan kualitas lingkungan, pemeliharaan sumber daya
alam;
4. konsolidasi tanah harus dilakukan dengan melibatkan
partisipasi aktif masyarakat.
TUJUAN, SASARAN DAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH
Melihat fenomena di setiap perkotaan dan perdesaan akan
ditemukan suatu penataan permukiman yang semrawut, terjadinya
tanah yang tidak ditata dengan baik, karena masyarakat tidak mau
peduli dengan kondisi tersebut, maka pemerintah mengeluarkan
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahu 1991 tentang Konsolidasi
Tanah.
Berkaitan dengan pengertian konsolidasi tanah menurut Pasal 1
PP Nomor 4 Tahun 1991, tujuan dari konsolidasi tanah adalah untuk
mencapai pemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatan
efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah.
Oleh karena itu, sasaran yang ingin dicapai dari konsolidasi
tanah adalah terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan
tanah yang tertib dan teratur ( pasal 2 ).
Ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
diatas, secara operasional diatur lebih lanjut dengan oleh Surat
Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-4245/1991 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang ditujukan kepada seluruh Kakanwil Pertanahan di
Indonesia.
Dalam poin 2 Surat Petunjuk tersebut dinyatakan bahwa :
Peningkatan yang demikian itu mengarah kepada tercapainya suatu
tatanan penggunaan dan penguasaan tanah yang tertib dan teratur.
Sasaran konsolidasi tanah terutama ditujukan pada wilayah –
wilayah sebagai berikut :
(1) Wilayah perkotaan :
(a) Wilayah permukiman kumuh;
(b) Wilayah permukiman yang tumbuh pesat secara alami;
(c) Wilayah permukiman yang mulai timbuh;
(d) Wilayah yang difrencanakan menjadi permukiman yang
baru;
(e) Wilayah yang relatif kosong di bagian pinggiran kota
yang diperkirakan akan berkembang sebagai daerah
permukiman.
(2) Wilayah pedesaan :
(a) Wilayah yang potensial dapat memperoleh perairan tetapi
belum jaringan irigasi;
(b) Wilayah yang jaringan irigasinya telah tersedia tetapi
pemanfaatannya belum merata;
(c) Wilayah yang berpengairan cukup baik maupun masih perlu
ditunjang oleh pengadaan jaringan jalan yang memadai.2
2 Supriadi SH.M.hum. op.cit hal.264
Sejalan dengan poin 2 Surat Petunjuk Kepala Badan Pertanahan
Nasional tersebut, maka pada poin 3 dari ketentuan tersebut
dinyatakn bahwa konsolidasi tanah meliputi kegiatan sebagai
berikut :
(1) Konsolidasi tanah perkotaan, meliputi :
(a) Pemilihan lokasi;
(b) Penyuluhan;
(c) Penjajakan kesepakatan;
(d) Penetapan lokasi konsolidasi tanah dengan surat
keputusan walikota/bupati;
(e) Pengajuan daftar usulan rencana kegiatan konsolidasi
tanah;
(f) Identifikasi subjek dan objek;
(g) Pengukuran dan pemetaan keliling;
(h) Pengukuran dan pemetaan rincian;
(i) Pengukuran topografi dan pemetaan penggunaan tanah;
(j) Pembuatan blok plan/pradesain tata ruang;
(k) Pembuatan desain tata ruang;
(l) Musyawarah tentang rencana penataan kaplingan baru;
(m) Pelepasan hak – hak atas tanah oleh para peserta;
(n) Penegasan tanah sebagai objek konsolidasi tanah;
(o) Staking out/realokasi;
(p) Konstruksi/ pembentukan badan jalan, dan lain – lain;
(q) Redistribusi; tanah/penertiban SK pemberian hak;
(r) Sertifikat.
(2) Konsolidasi Tanah di pedesaan kegiatan meliputi :
(a) Pemilihan lokasi;
(b) Penyuluhan;
(c) Penjajakan kesepakatan;
(d) Penetapan lokasi dengan Surat Keputusan
bupati/walikota;
(e) Identifikasi subjek dan objek;
(f) Pengajuan daftar usulan rencana kegiatan konsolidasi
tanah;
(g) Seleksi calon penerima hak;
(h) Pengukuran/pemetaan kapling;
(i) Pengukuran/pemetaan rincikan;
(j) Pengukuran topografi dan pemetaan tanah;
(k) Pembuatan blok plan/pradesain tata ruang;
(l) Pembuatan desain tata ruang;
(m) Musyawarah rencana penataan kapling baru;
(n) Pelepasan hak oleh pemilik tanah
(o) Penegasan lokasi sebagai tanah objek konsolidasi tanah;
(p) Staking/relokasi;
(q) Konstruksi/pembentukan prasarana umum dan lain – lain;
(r) Redistribusi tanah/penerbitan SK pemberian hak;
(s) Sertifikat.
Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan konsolidasi
tanah diarahkan pada tertibnya penggunaan tanah, tetapi juga
diarahkan untuk melakukan penataan kembali bidang – bidang tanah
tersebut. Hal ini sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional sebagai berikut :
Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dan sekaligus menyediakan
tanah untuk pembangunan prasarana dan fasilitas umum dilaksanakan pengaturan
penguasaan dan penatagunaan tanah dalam bentuk konsolidasi tanah di wilayah
perkotaan dan di pedesaan ( ayat (1) ). Kegiatan konsolidasi tanah meliputi penataan
kembali bidang – bidang tanah termasuk hak atas tanah dan atau penggunaan
tanahnya dengan dilengkapi prasarana jalan, irigasi, fasilitas lingkungan dan atau
serta fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan dengan melibatkan partisipasi
pemilik tanah dan atau penggarap lain.3
Pelaksanaan konsolidasi tanah disuatu daerah tetap
ditentukan oleh pemerintah setempat, misalnya bupati/walikota
dimana letak tanah yang akan dikonsolidasi tersebut. Namun
demikian, dalam penentuan wilayah konsolidasi tanah tersebut,
tetap mengacu pada penataan ruang daerah yang bersangkutan.
Selain itu, dalam pelaksanaan konsolidasi tanah ini, juga
diperlukan persetujuan dari pemilik atau penggarap tanah yang
didalam penguasaan masyarakat. Ketentuan ini sesuai pasal 4
dinyatakan bahwa :
Lokasi konsolidasi ditetapkan oleh bupati/walikota dengan mengacu kepada
rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah. Konsolidasi tanah dapat
3 Supriadi SH.M.hum. op cit hal.265
dilaksanakan apabila sekurang – kurangnya 85% dari pemilik tanah yang luasnya
meliputi sekurang – kurangnya 85% dari luas seluruh areal tanah yang akan
dikonsolidasi menyatakan persetujuannya.
Mencermati ketentuan pasal 4 diatas, wajar kalau suatu tanah
yang dikuasai oleh masyarakat kemudian akan dijadikan objek
konsolidasi mendapat persetujuan sekurang – kurangnya 85% dari
masyarakat yang menguasainya tersebut. Hal ini dimaksud untuk
menegah terjadinya kesalahpahaman hukum dikemudian hari.
Sementara itu, pelaksanaan konsolidasi tanah melibatkan
instansi sektoral, sehingga diperlukan organisasi sebagai
pelaksana operasionalnya. Dalam angka 4 surat petunjuk Kepala
Badan Nasional dinyatakan bahwa :
Karena konsolidasi tanah memerlukan koordinasi lintas sektoral sejak
perencanaan hingga pelaksanaannya, maka dibentuk tim pengendalian konsolidasi
tanah di tingkat provinsi dan tim koordinasi serta satuan tugas pelaksanaan
konsolidasi tanah di tingkat kabupaten/kota.
Secara opersional, konsolidasi tanah dilaksanakan oleh
instansi-instansi lain yang terkait dan masyarakat di bawah
koordinasi Gubernur untuk Daerah Tingkat I dan di bawah
Bupati/Walikota untuk Daerah Tingkat II ( Pasal 5 ayat 3 ).
Komposisi tim pengendalian dan satuan tugas pelaksanaan
konsoliadasi tanah adalah sebagai berikut :
1. Gubernur kepala daerah : sebagai pembina
2. Kepala Kanwil BPN : sebagai ketua
3. Ketua Bappeda Provinsi : sebagai wakil ketua
merangkap anggota
4. Kabid pengaturan penggunaan tanah : sebagai sekretaris
merangkap anggota
5. Karo pemerintahan : sebagai anggota
6. Kadis Kimpraswil : sebagai anggota
7. Kabid Hak atas tanah : sebagai anggota
8. Kabid pengukuran dan pendaftaran : sebagai anggota
tanah
Berkaitan dengan tim pengendalian dan satuan tugas konsolidasi
tanah, tim konsolidasi tanah tersebut memiliki tugas sebagai
berikut :
1. Melakukan pengendalian dan evaluasi perkembangan pelaksanaan
konsolidasi tanah.
2. Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
konsolidasi tanah dan melakukan langkah – langkah tindak
lanjut.
3. Memberikan bimbingan, pengarahan petunjuk kepada aparat
pelaksana konsolidasi tanah di kabupaten/kotamadya.
4. Lain – lain yang dianggap perlu.
Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kotamadya dibentuk tim
yang sama pada tingkat provinsi, yang komposisinya sebagai
berikut :
1. Bupati/walikota : sebagai ketua
2. Kepala kantor BPN : wakil merangkap anggota
3. Ketua Bappeda : wakil merangkap anggota
4. Karo pemerintahan : sebagai anggota
5. Kadis Kimpraswil : sebagai anggota
6. Kadis pertanian : sebagai anggota
7. Kadis Tata Kota : sebagai anggota
8. Camat setempat : sebagai anggota
9. Ka seksi PGT : sebagai anggota
10. Ka seksi PHT : sebagai anggota
11. Ka seksi PT : sebagai anggota
12. Lurah / kades setempat : sebagai anggota
13. Wakil pemilik tanah ( maks. 2 orang ) : sebagai
anggota
14. Ka pengaturan dan penguasaan tanah : sebagai
sekretaris merangkap anggota.
Berkaitan dengan susunan tim pengendalian konsolidasi tanah di
atas, tim konsolidasi tanah tingkat kabupaten/walikota sebagai
berikut :
1. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat.
2. Mengevaluasi dan mengarahkan penyusunan desain tata ruang.
3. Mengatur/mengarahkan peruntukan dan penggunaan tanah
pengganti biaya pelaksanaan (TPBP).
4. Memecahkan dan menangani masalah yang timbul dalam
pelaksanaan konsolidassi tanah.
5. Lain – lain yang dianggap perlu.
Selain tim konsolidasi tanah yang dibentuk di
kabupaten/kotamadya, pada tingkat kabupaten/kotamadya, juga
dibentuk satuan tugas (satgas) yang terdiri atas :
1. Kepala kantor BPN kabupaten/kota : sebagai ketua
2. Kepala seksi PPT : sebagai wakil
3. Kepala seksi PGT : anggota
4. Kepala seksi PHT : anggota
5. Seksi PT : anggota
6. Camat : anggota
7. Kepala Desa : anggota
Sumbangan Tanah untuk Pembangunan
Sumbangan tanah untuk pembanguan dalam rangka konsolidasi
tanah dilakukan oleh para pemilik tanah sesuai dengan
kemampuannya, baik dalam bentuk tanah maupun dalam bentuk uang.
Penetapan besarnya sumbangan tersebut didasarkan musyawarah
antara pemilik tanah itu sendiri. Hal ini sesuai ketentuan dalam
pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional ( BPN ).
Ketentuan pasal 6 Peraturan Kepala BPN ditindaklanjuti oleh
surat petunjuk kepala BPN No. 410 -4245 tanggal 7 Desember 1991.
Dalam surat petunjuk tersebut, dinyatakan dalam angka 6 poin 1
dinyatakan bahwa4 :
4 Supriadai SH.M.hum. Op cit.hal.267
Setiap peserta konsolidasi tanah dikenakan sumbangan tanah untuk
pembangunan yang besarnya ditentukan melalui musyawarah dengan para pemilik
tanah. Peserta konsolidasi tanah yang persil tanahnya terlalu kecil sehingga tidak
mungkin memberikan sumbangan tanah untuk pembangunan dapat mengganti
sumbangan tersebut dalam bentuk uang yang senilai atau bentuk lainnya, misalnya
tenaga kerja yang dapat dinilai dengan uang.
Sejalan dengan ketentuan dalam surat petunjuk Kepala BPN
diatas, maka penggunaan sumbangan tanah untuk pembangunan adalah
(a) Untuk prasarana jalan/fasilitas umum lainnya;
(b) Sebagai tanah pengganti biaya pelaksana ( TPBP ) atau
Cost Equivalent Land ( CEL).
Oleh karena itu, dalam pengelolaan tanah pengganti biaya
pelaksanaan dilakukan dengan tujuan :
a. Tanah pengganti biaya pelaksanaan adalah sumbangan tanah
untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk prasarana jalan
dan fasilitas umum lainnya.
b. Tanah pengganti biaya pelaksanaan diserahkan penggunaannya
kepada peserta konsolidasi tanah yang memiliki kapling kecil
atau kepda pihak lainnya dengan pembayaran kompensasi berupa
uang dengan jumlah yang ditetapkan berdasarkan musyawarah
para peserta konsolidasi tanah. Dalam penyerahan penggunaan
tanah itu peserta konsolidasi tanah yang kaplingnya kecil
tersebut, diprioritaskan. Penyerahan penggunaan tanah
pengganti biaya pelaksana konsolidasi tanah dilakukan oleh
Kepala Kantor pertanahan Kabupaten/kota dengan memberikan
Surat Izin Menggunakan Tanah ( SIMT ).
Mencermati dengan sungguh – sungguh terhadap pelaksanaan
konsolidasi tanah yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional diatas yang kemudian ditindaklanjuti dengan
dikeluarkannya surat petunku oleh Kepala Badan Pertanahan
Nasional, merupakan suatu kebijakan yang patut mendapatkan
dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Sebab tidak dapat
dipungkiri bahwa kesemrawutan yang terjadi di kota – kota dan
sebagian di pedesaan, akibat dari tidak adanya suatu penataan
penggunaaan, pengaturan tanah – tanah yang terdapat di suatu kota
tersebut. Hal ini disebabkan pada satu sisi pemerintah kurang
perhatian terhadap penataan terhadap penggunaan tanah tersebut,
di sisi lain masyrakat belum mengerti bagaimana mengatur dengan
baik mengenai penataan terhadap tanah yang tidak teratur
tersebut.
Untuk menjawab ketidaakterarutan mengenai tanah yang terdapat
di wilayah perkotaan dan di wilayah pedesaan tersebut, adalah
dilaksanakannya dengan konsisten terhadap pelaksanaan
konsolidasi tanah tersebut. Sebab pendekatan yang dilukakan
adalah pendekatan partisipasi dari masyrakat, dengan cara mencari
solusi yang terbaik terhadap penataan, penggunaan yan terdapat di
wilayahnya masing – masing.
Peralihan Hak dalam Konsolidasi
Pelepasan hak atas tanah dalam konsolidasi tanah adalah suatu
tindakan peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada
negara untuk ditata dalam konsolidasi tanah. Selanjutnya hak atas
tanah yang telah dikuasai negara tersebut ditata dan dikembalikan
lagi kepada pemilik tanah semula setelah dikurangi luas tanahnya
sesuai kesepakatan. Makna “kesepakatan” dalam konsolidasi tanah
adanya kesesuaian kehendak dari kedua belah pihak, dimana pihak
yang satu berjanji melaksanakan konsolidasi tanah, sedangkan
pihak yang lainnya berjanji untuk menyetujui rencana konsolidasi
tanah termasuk besaran persentase tanah yang akan disumbangkan.
Dengan demikian, pelepasan hak atas tanah dalam konsolidasi tanah
adalah peralihan hak atas tanah “bersifat sementara”. Sebaliknya
pelepasan hak atas tanah dalam pengadaan tanah yang dikenal
selama ini adalah peralihan hak untuk mengakhiri hak atas tanah.
Tindakan pelepasan hak atas tanah dalam konsolidasi tanah adalah
melalui penyerahan “Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dalam Rangka
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah” yang ditandatangani pemilik tanah
dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau petugas
yang ditunjuk. Langkah dalam pelepasan hak atas tanah adalah:
(a) pemilik tanah yang menyepakati pelaksanaan konsolidasi tanah
datang sendiri ke kantor pertanahan Kabupaten/Kota untuk membuat
surat pernyataan;
(b) apabila tanah tersebut sudah bersertifikat dan
diagunkan/jaminan kredit, maka harus ada persetujuan kreditur
yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota perlu memberitahukan secara tertulis
kepada kreditur dan selanjutnya diselesaikan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
(c) apabila tanah yang bersangkutan merupakan pemilikan bersama
misalnya suami-istri, maka yang menandatangani Surat Pernyataan
Pelepasan Hak adalah suami-istri (bersama-sama). Pada saat
pelepasan hak/penguasaan fisik, sertipikat dan bukti-bukti lain
diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
(d) tanah-tanah yang telah menjadi aset pemerintah persetujuannya
dari instansi yang bersangkutan.
Tindakan pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada
negara untuk menjadikan status tanah menjadi tanah yang langsung
dikuasai negara dalam konsolidasi tanah adalah “unik”. Keunikan
pertama, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang
mengatur model pelepasan hak atas tanah seperti itu. Dengan kata
lain model pelepasan hak atas tanah dalam konsolidasi tanah tidak
dikenal, baik berdasarkan BW, hukum adat, maupun atas dasar
Undang-Undang Pokok Agraria. Keunikan kedua, tanah hasil dari
pengurangan tanah semula adalah “Sumbangan Tanah Untuk
Pembangunan (STUP)” dengan tidak ada ganti rugi berupa uang.
Ganti rugi dalam konsolidasi tanah adalah ganti rugi berupa
lingkungan yang tertata rapi, semua tanah menghadap kejalan,
terdapatnya fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan kepastian
hak atas tanah berupa sertifikat yang diperoleh secara cuma-cuma
sebagai kompensasi atas tanah yang disumbangkan dalam konsolidasi
tanah.
Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan; pertama, ada perbedaan
antara pelepasan hak atas tanah dalam konsolidasi tanah yang
bersifat sementara dan pelepasan hak atas tanah dalam pengadaan
tanah yang merupakan peralihan hak untuk mengakhiri hak atas
tanah yang dikenal dalam hukum perdata seperti melalui jual beli,
tukar menukar, atau yang dikenal dalam hukum administrasi seperti
nasionalisasi, perampasan, pengambilalihan untuk kepentingan
landreform, ataupun melalui pencabutan hak atas tanah
(onteiguning) yang kemudian diganti rugi; kedua, keunikan
pelepasan hak atas tanah dalam konsolidasi tanah lebih disebabkan
latar belakang penggunaan model konsolidasi tanah yang diadopsi
dari negara lain (Taiwan).
TINDAKAN PEMERINTAH SEBELUM PELAKSANAAN KONSOLIDASI
Pembahasan tentang permasalahan sebelum pelaksanaan
konsolidasi tanah memegang peranan penting dalam pelaksanaan
kegiatan, dengan diketahuinya masalah yang muncul sebelum
pelaksanaan, maka Aparat pelaksanan dapat mengantisipasinya agar
kegiatan konsolidasi tanah dapat berlanjut ketahap pelaksanaan.
Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui sebelum
pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah pada umumnya terdiri dari
hal-hal, antara lain sebagai berikut :
Pemilihan Lokasi.
Kesalahan pemilihan lokasi merupakan kegagalan awal
pelaksanaan Konsolidasi Tanah, penentuan lokasi kegiatan tanpa
memperhatikan faktor tata ruang serta rencana prioritas
pembangunan daerah setempat ,merupakan tindakan gegabah, karena
dari segi yuridis, ketentuan tata ruang merekomendasikan bahwa
segala kegiatan pembangunan harus didasarkan pada Rencana Umum
Tata Ruang ( RUTR ) dengan segala turunannya yang diundangkan
melalui Perda setempat.
Pemilihan lokasi adalah serangkaian kegiatan penilaian
dengan menggunakan parameter – parameter tertentu terhadap lokasi
lokasi yang berpotensi, dengan pemberian nilai pembobotan /
perangkingan mulai dari urutan tertinggi hingga terendah, yang
akan dipilih kemudian sebagai lokasi yang paling berpotensi untuk
dilaksanakan kegiatan konsolidasi tanah.
Pelaksanaan Pemilihan lokasi.
Sebagaimana dipahami bahwa salah satu konsep dasar
pembangunan nasional adalah mengurangi kesenjangan pertumbuhan
antar wilayah dan pemerataan pembangunan keseluruh wilayah,
dengan tetap menekankan agar pembangunan yang dilaksanakan tetap
memperhatikan keserasian ekosistem dan pendukungnya. Dengan
arahan kebijakan ini maka koordinasi keseluruhan pembangunan
harus mencakup segi spasial ( spatial ), dan selanjutnya segi
spasial akan menjadi dasar bagi pencapaian keserasian dan
optimasi pemanfaatan ruang, dengan kata lain bahwa rencana tata
ruang merupakan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di daerah
yang menjamin agar keseluruhan kegiatan pembangunan di daerah
merupakan satu kesatuan pembangunan nasional.
Tata ruang pada intinya bermakna sebagai penataan penggunaan
ruang, atau perencanaan tata guna ruang yang bermaksud mengatur
pemanfaatan ruang secara berencana, terarah, terpadu dan
berkesinambungan. Tata ruang mempunyai ruang lingkup yang luas
yang meliputi daratan, perairan dan udara, sehingga penataan
ruang bukanlah tindakan yang sekedar mengalokasikan ruang untuk
suatu kegiatan tertentu saja, melainkan penempatan kegiatan
penggunaan tanah, air dan ruang udara sesuai kemampuannya.
Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik penggunaan
ruang, yaitu suatu pendekatan bidang kegiatan terhadap bidang
kegiatan lainnya yang lebih sesuai dengan karakter ruang
tersebut, sehingga dapat dicapai optomalisasi usaha sesuai
kondisi ruang demi menjamin pemanfaatan atas ruang dimaksud.
Dengan mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang ( RUTR ),
teristimewa Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR ) dan Rencana Tehnik
Ruang ( RTR ), serta rencana prioritas pembangunan daerah, maka
pemilihan lokasi kegiatan Konsolidasi Tanah dapat diarahkan pada
wilayah – wilayah dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
a. Wilayah pemukiman kumuh.
b. Wilayah pertanian yang kurang didukung sarana pertanian.
c. Wilayah pemukiman yang mulai tumbuh.
d. Wilayah yang direncanakan menjadi pemukiman baru.
e. Wilayah yang relatif kosong, bagian pinggiran kota yang
diperkirakan akan berkembang.
Selain faktor RTUTR dan rencana prioritas pembangunan daerah ,
masih terdapat faktor lain yang juga tak kalah penting
diperhitungkan untuk menentukan kelayakan objek konsolidasi
tanah, antara lain sebagai berikut :
Aksesibilitas lokasi.
Animo masyarakat.
Jumlah bidang tanah.
Keadaan topografi yang relatif datar.
Semakin banyak pemilik tanah / semakin luas lokasi,semakin
ideal.
Salah satu kunci penentu agar pelaksanaan Konsolidasi Tanah
memiliki multiplier effect bila dikaitkan dengan tata ruang daerah
adalah pemilihan lokasi yang dilakukan secara
cermat.
Oleh karena itu kriteria dari setiap pemilihan lokasi menjadi
penting. Pemilihan parameter lokasi yang berwawasan Tata Ruang
adalah rekayasa suatu strategi integral dari strategi umum
pembangunan wilayah / daerah.
Permasalahan fundamental pada pemilihan lokasi terletak pada
bagaimana memprediksi bahwasanya suatu lokasi akan berkembang
sesuai dengan arah dan tujuan konsolidasi tanah yang berbasis
tata ruang dan searah dengan rencana prioritas pembangunan
daerah. Para pakar, antara lain seperti : Ir. Kurdinanto Sarah,
M.Sc, Edgar M Hover dll, merekomendasikan bahwa idealnya
penilaian wilayah dalam rangka pemilihan lokasi dilakukan melalui
metode pendekatan secara mikro dan pendekatan secara mikro.
a. Pendekatan secara Makro.
Tujuan penilaian melalui pendekatan secara makro ini adalah
untuk memastikan secara makro apakah wilayah dimaksud layak atau
tidak layak. Pendekatan makro adalah pendekatan yang
berdasarkan : azas kesesuaian ( sesuai dengan RUTR ), azas
kesempatan ( potensial berkembang ) dan azas keberlanjutan
( integral dengan program pembangunan lainnya ), yang mengacu
pada tiga hal dasar yaitu :
1.kebutuhan masyarakat
2.pertumbuhan dan perubahan
3.adanya konsiderasi lingkungan
Adany
Jadi pendekatan makro
digunakan mengawali penilaian pemilihan lokasi konsolidasi tanah
yang bertujuan untuk melihat secara keseluruhan apakah wilayah
penilaian mempunyai daya tarik atau tidak, dengan kata lain
penilaian wilayah melalui pendekatan makro akan menghasilkan
Wilayah Potensial dan Wilayah Tidak Potensial.
b. Pendekatan secara Mikro.
Selanjutnya wilayah potensial, hasil penilaian dari
pendekatan secara makro dianalisis dengan pendekatan mikro.
Tinjauan pendekatan mikro adalah analisis dari sudut rencana
tapak ( site plan ) yang merupakan pendorong keberhasilan program,
kepercayaan masyarakat terhadap sebuah program sangat tergantung
pada kekuatan dalam menganalisa tapak, bahwasanya masyarakat
pemilik tanah tidak akan dirugikan akan tetapi justru akan
diuntungkan pada kemudian hari, inilah sasaran dari pendekatan
mikro.
Rancana tapak ( site plan ) yang merupakan hasil study planologis
adalah gambaran yang menampung aspirasi yang tidak merugikan
pemilik tanah, oleh karena itu dalam meninjau secara mikro hal –
hal yang berkaitan dengan program perlu memperhatikan beberapa
tinjauan sebagai berikut :
1. Mempunyai aksesibilitas yang relatif mudah, misalnya
lokasi berada disisi jalan yang menghubungkan kawasan lain
sehingga lokasi dimaksud cenderung berkembang cepat,
2. Pada awal, harga tanah berada pada tingkat relatif
rendah, sehingga sangat memungkinkan bertambah tinggi setelah
tersedianya infrastruktur dikemudian hari,
3. Telah terjadi proses fragmentasi yang amat tinggi,
4. Jumlah kepemilikan tanah relatif banyak, terbuka dan
luas kepemilikannya relatif cukup untuk dikonsolidasikan,
serta luas bidang tanah setelah program, sesuai dengan
rencana tata ruang setempat,
5. Pada setiap individu pemilik tanah, tidak terdapat
sengketa, baik mengenai batas maupun kepemilikannya,
6. Analisis biaya pembangunan, jadwal, dan prospek kenaikan
nilai / harga tanah setelah program.
Penilaian wilayah dari sudut pendekatan mikro akan
menghasilkan Wilayah Potensial Detail.
Selanjutnya hasil penilaian wilayah dari kedua pendekatan
tersebut diatas masing – masing diberi bobot penilaian guna
penetapan rangking, semakin besar nilainya semakin tinggi
rangkingnya sebagai prioritas lokasi kegiatan Konsolidasi
Tanah. Dengan tersusunnya lokasi –lokasi potensial diharapkan
kegagalan awal akibat salah memilih lokasi dapat diminimalisir.
Namun berdasarkan kasus yang terjadi, kegagalan juga dapat
terjadi atas lokasi yang telah sesuai dengan tata ruang setempat,
dengan adanya perubahan - perubahan pada lokasi yang
bersangkutan, seperti perubahan :
1. Fisik tanah ; biasanya terjadi pada tanah pertanian
eks HGU, yang sudah diduduki dan dikuasai oleh para
penggarap dan digunakan sebagai tanah pemukiman
(pekarangan ).
2. Yuridis ; terbit Perda baru yang merubah penggunaan
tanah lokasi dimaksud.
Berdasarkan pengalaman pelaksanaan konsolidasi tanah di
seluruh Indonesia, bahwa pada umumnya kegagalan juga turut
disebabkan oleh pemilihan lokasi secara sederhana, hanya
berdasarkan kemauan masyarakat lokasi yang bersangkutan saja,
tanpa mengikuti kaidah sebagaimana yang direkomendasikan oleh
para pakar.
Dalam pelakasaan kegiatan Pemilihan Lokasi
hendaknya memperhatikan rekomendasi para Pakar, yaitu didahului
dengan kegiatan Penilaian Lokasi melalui pendekatan makro dan
mikro, yang akan menghasilkan wilayah potensial detail, dan
selanjutnya diberikan nilai pembobotan / perengkingan sebagai
lokasi prioritas konsolidasi tanah, yang diharapkan akan
mengurangi / meminimalisir kesalahan pemlihan lokasi.
Penyuluhan
Adapun masalah / hambatan konsolidasi tanah yang berkaitan
dengan penyuluhan adalah keterbatasan kemampuan aparat BPN di
daerah, terlebih keterbatasan kemampuan non tehnis seperti
tehnik komunikasi yang merupakan salah satu unsur utama
penyuluhan, keterbatasan media komunikasi seperti multi media,
keterbatasan jangka waktu penyuluhan yang dianggap terlalu
singkat, keterbatasan penguasaan materi konsolidasi tanah dan
lain sebagainya.
Kegiatan penyuluhan merupakan salah bentuk bentuk
komunikasi yang sering digunakan oleh Pemerintah untuk
menyampaikan suatu pesan / informasi kepada masyarakat banyak,
dalam penyuluhan komunikasi yang terjadi adalah dua arah,
sehingga diharapkan pesan / informasi yang disampaikan dapat
dipahami betul oleh masyarakat.
Istilah penyuluhan berasal dari kata suluh, yang berarti
obor, alat penerangan, sehingga istilah penyuluhan berarti
penerangan. Apa yang diterangkan dalam penyuluhan adalah gagasan
tentang sesuatu yang belum dimengerti oleh masyarakat, sehingga
mereka membutuhkan penjelasan / penerangan yang sejelas mungkin /
gamblang dari pihak Penyuluh.
Agar pesan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, maka
mau tidak mau tenaga Penyuluh adalah orang yang benar – benar
menguasai materi tentang gagasan yang akan disampaikan kepada
masyarakat, sehingga penjelasan yang akan diberikan bersifat
lengkap / tidak sepotong – sepotong, dan mampu menjawab semua
persoalan yang berkaitan dengan substansi dimaksud, sehingga jika
masyarakat terpuaskan. Selain tenaga Penyuluh, terkadang
diperlukan alat bantu yang dapat menunjang keberhasilan
komunikasi, seperti multimedia, film, Penterjemah ( Interpreter /
Translator ), dan lain – lain, sehingga gagasan tentang kegiatan
konsolidasi tanah dengan segala aspeknya dapat dipahami dengan
baik.
Program Konsolidasi Tanah adalah program
terpadu antara Pemerintah dengan Masyarakat, sehingga
pelaksanaannya mau tidak mau harus melibatkan kedua belah pihak
secara harmonis. Substansi pokok dalam konsolidasi tanah adalah
partisipasi masyarakat untuk menyumbangkan sebagian tanah
miliknya yang selanjutnya akan dipakai untuk pembangunan
fasilitas umum dan sosial ( Fasum / Fasos ).
Salah satu upaya guna mendapatkan kemauan dan
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan konsolidasi
tanah adalah melalui kegiatan penyuluhan. Melalui penyuluhan
masyarakat diberikan penjelasan mengenai manfaat, keuntungan dan
tujuan konsolidasi tanah dengan segala aspeknya, terutama
partisipasi masyarakat untuk menyumbangkan sebagian tanah
miliknya untuk dibangun sebagai lokasi fasilitas umum dan
fasilitas sosial ( FASUM / FASOS ).
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka
penyuluhanpun memegang peranan kunci keberhasilan pelaksanaan
kegiatan konsolidasi tanah. Berhasil tidaknya konsolidasi tanah,
ikut ditentukan oleh kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan pada
tahap – tahap awal kegiatan.
Melalui upaya penyuluhan, masyarakat dapat memiliki
gambaran tentang konsolidasi tanah yang utuh dengan segala
implikasinya, sehingga mereka dapat segera memberikan respon
penilaian sekaligus keputusan berpartisipasi dalam kegiatan
dimaksud.
Berdasarkan pelaksanaan konsolidasi tanah di seluruh
Indonesia, bahwa pada umumnya kegagalan juga turut disebabkan
oleh penyuluhan yang kurang berhasil. Hal ini nampak pada awal
kegiatan, masyarakat nampak antusias, namun ditengah kegiatan
mereka menarik diri dan menolak ikut berpartisipasi dengan
berbagai alasan.
Adapun kelemahan dari penyuluhan adalah sebagai berikut :
a. Terbatasnya kemampuan petugas penyuluh yang cukup
berkualitas ,baik penguasaan materi konsolidasi tanah maupun
tehnis penyuluhan yang baik, sehingga BPN RI perlu membekali
aparat pelaksanana di daerah dengan tambahan keterampilan
yang cukup melalui pendidikan dan latihan jangka pendek.
b. Jangka waktu yang disediakan / dialokasikan untuk
kegiatan penyuluhan amat singkat, sehingga penyuluhan
dilaksanakan hanya beberapa kali saja sebelum pelaksanaan
ketahap selanjutnya, padahal disisi lain, kegiatan
konsolidasi tanah adalah kegiatan lintas sektoral, yang
memerlukan waktu yang cukup.
Sebagai perbandingan, kegiatan penyuluhan konsolidasi
tanah di Taiwan ( salah satu negara yang sukses menyelenggarakan
konsoliasi tanah ) persiapan pelaksanaan termasuk kegiatan
penyuluhan dilaksanakan selama satu ( 1 ) tahun penuh, sehingga
masyarakat benar – benar memahami apa makna dan tujuan
konsolidasi tanah, serta manfaat dan keuntungan apa saja yang
akan diperoleh oleh masyarakat, baik secara pribadi maupun
berkelompok.
Agar penyuluhan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang
diharapkan, maka ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian,
antara lain sebagai berikut :
a. Hendaknya tenaga penyuluh benar – benar menguasai
materi / substansi yang akan disampaikan kepada masyarakat.
b. Jangan ragu untuk menggunakan alat bantu, seperti
multimedia dan lain sebaginya.
c. Bila perlu menggunakan jasa Jurubahasa / Interpreter
setempat.
b. BPN Pusat hendaknya melengkapi Personilnya dengan berbagai
macam keterampilan tehnis dan non tehnis melalui DIKLAT
Tehnis Konsolidasi Tanah maupun Keterampilan Non Tehnis
seperti : Komunikasi Massa, Psikologi, dan lain sebagainya.
e. BPN Pusat perlu memikirkan dan merumuskan kembali jangka
waktu penyuluhan yang terlalu singkat, ( jika dibandingkan
dengan Negara Taiwan yang sukses melaksanakan konsolidasi
tanah ), untuk disesuaikan kembali melalui peraturan yang
baru.
Persetujuan Peserta.
Hambatan / kesulitan pelaksanaan kegiatan konsolidasi yang
dikaitkan dengan persetujuan peserta adalah besaran persentasi 85
%, dianggap terlalu sulit untuk didapatkan, dan masyarakat
peserta yang tidak setuju namun lokasi tanahnya menyebar secara
sporadik dalam lokasi konsolidasi tanah.
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah baru dapat dilaksanakan apabila
telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat pemilik yang
menjadi peserta sekurang – kurangnya 85 % dan luas tanahnya
meliputi sekurang – kurangnya 85 % dari areal yang akan
dikonsolidasi ( Pasal 4 ayat 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 / 1991 ).
Persetujuan masyarakat yang disyaratkan sebesar minimal 85%
dianggap terlalu tinggi sehingga sulit dicapai. Dalam praktek
pelaksanaannya dibutuhkan waktu yang panjang nan berliku untuk
memperoleh persetujuan dimaksud.
Secara filosofis angka 85% ini bermakna sebagai ”persetujuan
mayoritas” yang hanya akan digunakan sebagai acuan untuk menilai
kesiapan / animo masyarakat setempat untuk menerima kegiatan
konsolidasi tanah.
Dengan perkataan lain bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah akan
lebih aman jika didasarkan atas persetujuam mayoritas.
Pelaksanaan Persetujuan Peserta.
Adapun hal-hal yang menyebabkan sulitnya mendapatkan
persetujuan mayoritas dimaksud antara lain adalah :
a. Kekurangpahaman masyarakat terhadap arti dan manfaat
Konsolidasi Tanah.
b. Ketidakrelaan masyarakat menyumbangkan tanahnya untuk
STUP dengan berbagai alasan.
c. Pemilik Tanah sesungguhnya domisilinya tidak diketahui
secara pasti.
Dengan tidak dicapainya persetujuan mayoritas dari
masyarakat, tentunya pelaksanaan konsolidasi tanah pada lokasi
yang sudah terpilih tidak dapat dilaksanakan.
Guna mengatasi / mengantisipasi kesulitan – kesulitan yang
berhubungan dengan persetujuan peserta, terdapat beberapa hal
yang perlu mendapat perhatian serius, seperti :
a. BPN Pusat harus mempertimbangkan kembali besaran
persentasi 85 % yang amat sulit dicapai ( sebagai bahan
perbandingan, Jepang, salah satu negara yang sukses
melaksanakan konsolidasi tanah, menetapkan persetujuan
peserta hanya sebesar 60 % saja ).
b. BPN ( Pusat dan Daerah ) harus lebih giat melakukan
sosialisasi mengenai manfaat dan keuntungan konsolidasi tanah
bagi masyarakat perorangan maupun keseluruhan.
Manfaat Konsolidasi Bagi Masyarakat
- Peningkatan kualitas kehidupan dengan lingkungan yang teratur,
tertib dan sehat.
- Peningkatan harga tanah meningkatkan nilai aset pribadi.
- Meningkatkan Efisiensi dan Produktifitas Lahan.
- Memperoleh kepastian akan hak atas tanah.
Manfaat Konsolidasi bagi Pemerintah
- Terciptanya lingkungan kota yang lebih teratur, tertib, dan
sehat
- Menertibkan administrasi pertanahan
- meningkatkan efisiensi dan produktifitas tanah.
- dan lain sebagainya
BAB IV
PENUTUP
SARANSehubungan dengan kesulitan pelaksanaan kegiatan konsolidasi
tanah sebagaimana tersebut diatas, disarankan agar :
BPN Pusat segera meningkatkan dasar hukum konsolidasi tanah dari
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional menjadi Peraturan
Pemerintah ( PP ) atau Peraturan Presiden ( PERPRES ) agar dapat
mengikat semua Instansi Pemerintah yang terkait dalam kegiatan
konsolidasi tanah.
Dalam peraturan perundangan baru seperti tersebut diatas, harus
ada rumusan jalan keluar bagi Masyarakat yang tidak setuju
( diluar 85 % ), mengingat bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah di
Indonesia tidak bersifat wajib, melainkan bersifat sukarela.
Perkembangan kawasan perkotaan berlangsung sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi yang kemudian mendorong pertumbuhan berbagai
aktivitas terkait termasuk bidang permukiman. Di satu sisi
terjadi peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi yang
menyebabkan pertambahan permintaan tanah untuk permukiman dan
perumahan beserta fasilitas umum lainnya, sementara di sisi lain
penyediaan tanah tidak mengalami pertambahan. Hal ini menjadi
salah satu penyebab tidak terkendalinya penggunaan tanah dan
tidak memadainya infrastruktur yang mendukung suatu kota sehingga
kota tidak menjadi suatu kawasan yang nyaman bagi penduduknya.
Banyaknya kepentingan komponen dan kompleksnya pemanfaatan
ruang di kawasan perkotaan menambah rumitnya permasalahan
penataan ruang di kawasan perkotaan. Berkaitan dengan masalah
tersebut, dibutuhkan suatu mekanisme perencanaan kawasan
perkotaan dan pelaksanaannya yang dapat berjalan selaras dengan
perkembangan dan pertumbuhan suatu kota. Konsolidasi tanah,
mengupayakan penataan kembali penguasaan, pemilikan dan
penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah serta
mengupayakan pengadaan tanah untuk pembangunan yang meningkatkan
kualitas lingkungan hidup dan pemeliharaan sumber daya alam,
dapat menjadi salah satu sarana pembangunan kawasan perkotaan.
Konsep yang memadukan aspek legalitas penguasaan tanah dan aspek
fisik penggunaan tanah ini, yang melibatkan masyarakat secara
langsung dalam pelaksanaannya, diharapkan dapat mengurangi
masalah pertumbuhan kota yang tidak terkendali. Di samping itu,
konsolidasi tanah dapat pula menjadi instrumen yang efektif dalam
pelaksanaan penataan ruang kawasan perkotaan, salah satunya dalam
menjalankan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang.
Berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi
daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menggunakan
konsolidasi tanah sebagai salah satu sarana dalam pembangunan
kawasan perkotaannya. Daerah diharapkan dapat memetik manfaat
dari penerapan konsolidasi tanah ini yaitu berupa kawasan
perkotaan yang teratur, tertib dan sehat dengan didukung sarana
dan prasarana yang menunjang kawasan tersebut dengan selalu
memperhatikan tata ruang wilayah dan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaannya.
Untuk mencapai hal yang diharapkan tersebut, berbagai kendala
yang masih mungkin ditemui dalam pelaksanan konsolidasi tanah,
seperti aspek peraturan perundangan, kelembagaan, dan pembiayaan,
perlu diantisipasi dan diatasi guna menjamin kelancaran dan
kesuksesan pelaksanaan konsolidasi tanah dalam pembangunan dan
penataan ruang kawasan perkotaan.
KESIMPULAN
Tujuan dari konsolidasi tanah sebagai kebijakan pemerintah
mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta
usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk
peningkatan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam
adalah untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal melalui
peningkatan efisiensi dan prodiktifitas penggunaan tanah, artinya
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk
kepentingan masyarakat agar terwujud suatu tatanan pengauasan dan
penggunaan tanah yang tertib dan teratur.
Hal ini bukan berarti pemerintah dapat dengan sewenag-wenang
mengambil tanah milik masyarakat dengan alasan untuk pembangunan
tetapi pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan kesepakat
bersama antara pemerintah dengan peserta konsolidasi
tanah/masyarakat yang nantinya tanah objek konsolidasi tersebut
akan diserahkan kembali kepada pemilik Hak Atas Tanah baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Secara langsung artinya hak Atas Tanah akan diberikan kepada
peserta konsolidasi tanah sesuai dengan rencana penataan kapling
yang disetujui oleh yang bersangkutan. Diserahkan secara tidak
langsung artinya tanah tersebut dijadikan sarana dan prasarana
umum, misalnya untuk pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya
yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Hal ini merupakan penerapan dari asas tanah mempunyai fungsi
social, yaitu keselarasan antara kepentingan individu dengan
kepentingan social. Jadi, hak masyarakat atas tanahnya tetap
terlindungi dan tidak terjadi otoritarianisme yang dilakukan oleh
pemerintah di bidang agrarian khususnya di bidang pertanahan.
Daftar Pustaka
Supriadi,SH.M.Hum ,2006.”Hukum agraria”.Edisi pertama.Jakarta : Sinar
grafika
-htpps://akbarabdulfattah.wordpress.com/201311/13/konsolidasi-lahan-1/
-htpps://erestajaya.blogspot.com/2009/01/penataan-tanah-dan-lingkungan-melalui.html
-htpps://okkyirmanita.blogspot.com/2011/04/upaya-peningkatan-nilai-ekonomi-tanah.html