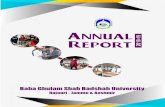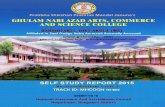Ghulam proposal penelitian
Transcript of Ghulam proposal penelitian
UJI EFEKTIVITAS BERBAGAI BENTUK INOKULUM RhizobakteriIndigenous MERAPI DAN METODE APLIKASI TERHADAP HASIL
TANAMAN PADI GOGO
Usulan Penelitian
Diajukan oleh :Cakra Ghulam Zatnicko
20110210020Program Studi Agroteknologi
KepadaFAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Usulan Penelitian
UJI EFEKTIVITAS BERBAGAI BENTUK INOKULUM RhizobakteriIndigenous MERAPI DAN METODE APLIKASI TERHADAP HASIL
TANAMAN PADI GOGO
Yang diajukan oleh`
Cakra Ghulam Zatnicko20110210020
Program Studi Agroteknologi
telah disetujui/disahkan oleh:
Pembimbing Utama
Ir. Agung Astuti M. Si
NIP.19620923199303133017Tanggal.......................
Pembimbing Pendamping
Ir. HariyonoNIK. Tanggal........................
Mengetahui:iii
Ketua Program Studi Agroteknologi
Dr. Innaka Ageng R., SP. MP
NIK.133.050 Tanggal........................
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Produktivitas beras di Indonesia terus meningkat,
hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat konsumsi
masyarakat terhadap makanan pokok ini. Pada tahun 2011
tingkat konsumsi beras penduduk Indonesia mencapai 139
kg/orang/tahun dengan jumlah penduduk mencapai 241 juta
jiwa, sehingga kebutuhan akan beras sebesar 33,49 juta
ton beras (BPS, 2011). Kebutuhan ini akan terus
bertambah seiring meningkatnya jumlah penduduk dengan
rata-rata laju pertumbuhan 1,49% per tahun. Peningkatan
jumlah penduduk ini, akan mengakibatkan terjadinya
peningkatan kebutuhan area pemukiman penduduk dan
pengurangan luasan lahan pertanian. Menurut Dirjen
Pengelolaan Lahan dan Air (2005) setiap tahunnya
sekitar 187.720 hektar sawah beralih fungsi
kepenggunaan lain terutama di Pulau Jawa. Hal tersebut
akan menjadi ancaman bagi ketahanan pangan national.
Disamping pengaliah fungsian lahan, masih ada beberapa
factor lain yang juga menjadi ancaman bagi ketahananiv
pangan nasional, seperti rusaknya infrastruktur
pengairan dan terjadinya perubahan iklam (Climate Change)
yang tidak menentu.
Salah satu perubahan iklim yang berdampak pada
gagalnya produksi beras adalah kemarau panjang yang
mengakibatkan lahan sawah kering. Bappenas (2010)
menyatakan bahwa lahan sawah di beberapa wilayah
Sumatra dan Jawa rentan terhadap bahaya kekeringan, 74
ribu ha diantaranya sangat rentan dan sekitar satu juta
ha rentan terhadap kekeringan. Masalah kekeringan lahan
sawah akibat perubahan iklim ini sulit untuk diatasi
dan sangat berdampak besar terhadap penurunan produksi
beras nasional. Sehingga perlu adanya peran teknologi
pertanian, seperti menambahkan mikroorganisme yang
dapat menyediakan asupan makanan untuk tanaman pada
kondisi cekaman kekeringan atau mengembangkan jenis dan
varietas tanaman pangan yang toleran terhadap stress
lingkungan, seperti kenaikan suhu udara, kekeringan,
banjir dan salinitas. Salah satu varietas padi yang
tahan terhadap kekeringan adalah padi gogo beras merah
segreng.
Di Indonesia penanaman padi gogo beras merah
segreng masih jarang, salah satu daerah yang menanam
padi beras merah ini adalah daerah istimewa Yogyakarta
(DIY). Padahal kandungan gizi yang terkandung di dalam
beras merah memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan
v
tubuh manusia. Dari hasil penelitian Fajar_Indriyani
dkk (2013) pada 100 gram beras merah memiliki kandungan
gizi yang terdiri atas protein 7,5 g, lemak 0,9 g,
karbohidrat 77,6 g, kalsium 16 mg, fosfor 163 mg, zat
besi 0,3 g, vitamin B1 0,21 mg dan antosianin.
Antosianin didalam beras merah adalah senyawa fenolik
yang masuk kelompok tinggi flavonoid yang berperan
penting, baik bagi tanaman itu sendiri maupun bagi
kesehatan manusia. Peran bagi kesehatan manusia dapat
mencegah beberapa penyait hati (hepatitis), kanker
usus, stroke, diabetes, sangat esensial bagi fungsi
otak dan mengurangi pengaruh penuaan otak. Kandungan
antosianin pada setiap gram padi beras merah masih
sangat beragam dan berkisar antara 0,34-93,5 µg
(Damanhuri; 2005; Herani dan Rahardjo, 2005). Tingginya
manfaat beras merah bagi kesehatan tubuh manusia,
seharusnya mendorong para petani untuk
membudidayakannya lebih luas lagi di setiap daerah di
Indonesia. Selain itu, beras merah padi gogo segreng
merupakan salah satu varietas yang tahan terhadap
kekeringan. Dari hasil penelitian Agung_Astuti dkk,
(2014) padi gogo segreng yang ditanam di lahan marginal
dan tanpa perlakuan dapat menghasilkan 1,30 ton/ha.
Hasil tersebut masih dapat ditingkatkan apabila ada
perlakuan dalam proses budidaya padi gogo segreng.
vi
Salah satu caranya yaitu dengan menambahkan
mikrobiologi berupa pupuk hayati pada tanah marginal.
Pada tahun 2012 Agung_Astuti menemukan adanya
mikrobia yang dapat tumbuh dan bertahan pada perakaran
rumput pioneer pasca erupsi gunung Merapi Yogyakarta pada
tahun 2010. Hasil identifikasi dan karakterisasi
menunjukan bahwa Rhizobakteri indigenous Merapi memiliki
kemampuan osmotoleran hingga >2,75 M NaCl serta
memiliki kemampuan Nitritikasi, Amonifikasi dan
Melarutkan Posphat (Agung_Astuti dkk,2013). Isolat
Rhizobakteri indigenous Merapi memiliki potensi untuk
dimanfaatkan sebagai pupuk hayati, khususnya pada
tanaman padi di lahan yang mengalami keterbatasan air.
Aplikasi Rhizobakteri indigenous Merapi pada tanaman padi
IR-64 menggunakan inokulum pada medium Luria Bertani
Cair (LBC) 2 ml/bibit, menunjukan hasil yang baik dalam
peningkatan pertumbuhan vegetatif tanaman padi yang
bertahan tanpa penyiraman hingga 6 hari (Agung_Astuti
dkk, 2013). Sedangkan inokulum Rhizobakteri indigenous
Merapi diaplikasikan kembali kepada tanaman padi gogo
varietas segreng, Ciherang dan IR-64 untuk melihat
hasil produksi padi, hasil aplikasi tersebut menunjukan
bahwa inokulum Rhizobakteri indigenous Merapi pada padi gogo
dengan varietas segreng mampu menghasilkan produksi
lebih baik hingga mencapai 1,78 ton/ha lebih banyak
30,5% dibandingkan dengan hasil varietas Ciherang dan
vii
34,6% dibandingkan dengan hasil IR-64 (Agung_Astuti
dkk, 2014).
Pada tahun 2014, Agung_Astuti dkk melanjutkan
penelitian metode aplikasi inokulum Rhizobakteri indigenous
Merapi pada tanaman padi IR-64 dengan menggunakan
inokulum padat dan cair. Penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan jenis carrier yang baik sebagai pembawa
mikroorganisme sekaligus menjadi tempat hidup bagi
populasi Rhizobakteri indigenous Merapi agar tetap
mempertahankan efektivitasnya sebagai pupuk hayati
hingga jangka waktu yang cukup lama. Dari hasil
penelitian tersebut menunjukan bahwa metode aplikasi
dengan inokulum padat yaitu perlakuan gambut+kaolin
(2:1 w:w) mampu meningkatkan proliferasi akar tanaman
dan meningkatkan populasi tanaman padi IR-64. Sedangkan
metode aplikasi menggunakan inokulum cair, mendapatkan
hasil baik pada perlakuan air kelapa 50%+ air rendaman
kedelai 50%. Perlakuan tersebut dapat meningkatkan
pertumbuhan tanaman padi IR-64 sebanyak 57,44 cm.
B. Perumusan Masalah
1. Belum diketahuinya metode aplikasi Rhizobakteri
indigenous Merapi yang paling baik antara inokulum
padat dan inokulum cair terhadap hasil tanaman padi
gogo.
viii
C. Tujuan
1. Mempelajari pengaruh metode aplikasi inokulum
Rhizobakteri indigenous Merapi terhadap hasil tanaman
padi gogo.
2. Menentukan jenis carrier terbaik terhadap tanaman
padi yang mengalami cekaman kekeringan.
ix
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Budidaya Tanaman Padi (Oryza sativa)
Padi diklasifikasikan sebagai Kingdom Plantae,
Divisio Spermatophyta, Subdivisio Angiospermae, Kelas
Monocotyledoneae, Ordo Poales, Familia Poaceae, Genus
Oryza, Spesies Oryza sativa. Tanaman padi dapat tumbuh di
daerah beriklim panas yang lembab, memerlukan curah
hujan rata-rata 200 mm/bulan dengan distribusi selama 4
bulan, sedangkan pertahun sekitar 1.500-2.000 mm. Suhu
yang panas berpengaruh terhadap kehampaan pada biji,
dan temperatur yang sesuai bagi tanaman padi yaitu pada
suhu 23oC. Tanaman padi memerlukan penyinaran matahari
penuh tanpa naungan (Bappenas, 2000).
Pertumbuhan padi dibagi ke dalam tiga fase yaitu
vegetatif, generatif dan pematangan. Fase vegetatif
ditandai dengan pertumbuhan jumlah anakan, tinggi
tanaman, jumlah, bobot dan luas daun. Padi IR 64 dengan
umur tanam 115 hari memiliki fase vegetatif 45 hari.
Sistem perakaran terdiri dari akar primer dan beberapa
akar sekunder, termasuk akar lateral dan akar adventitious.
Munculnya daun yang menembus keluar melalui kleoptil
terjadi pada hari ke-2 dan ke-3 setelah benih disebar
dipersemaian (Makarim dan Suhartatik, 2009).
Benih terus berkecambah menjadi bibit hingga hampir
keluar anakan pertaman. Selama pertumbuhan tanaman
10
muda akan terbentuk akar seminal dan lima daun dan
tunas akan terus tumbuh hingga dua daun akan terbentuk.
Kecepatan pertumbuhan daun yaitu 1 daun tiap 3-4 hari
pada tahap awal pertumbuhan, kemudian akan tumbuh akar
sekunder membentuk perakaran serabut permanen yang
menggatikan radikula dan akar seminal sementara.
Pembentukan anakan berlangsung sejak munculnya anakan
pertama hingga pembentukan anakan maksimum pada hari
ke-30 setelah tanaman dipindah dari persemaian. Tanaman
akan memanjang dan aktif membentuk anakan, hingga
memasuki pemanjangan batang (Makarim dan Suhartatik, ,
2009).
Fase reproduktif ditandai dengan memanjangnya
beberapa ruas teratas batang tanaman, berkurangnya
jumlah anakan, munculnya daun bendera, bunting
11
12
dan pembungaan. Pada saat tahap bunting, ujung daun
akan layu karena tua dan kemudian mati dan akan
terlihat anakan non produktif pada dasar tanaman.
Inisiasi primordia (bakal malai) biasanya dimulai 30
hari sebelum heading (keluarnya bunga atau malai) dan
waktunya hampir bersamaan dengan pemanjangan ruas-ruas
batang yang terus berlanjut sampai berbunga sehingga
stadia primordia disebut juga stadia pemanjangan ruas.
Keluarnya malai ditandai dengan munculnya ujung malai
dari pelepah daun bendera (Makarim dan Suhartatik, ,
2009).
Fase pematangan terjadi saat gabah mulai terisi
dengan cairan kental berwarna putih susu. Malai akan
mulai menghijau dan merunduk dan pelayuan pada anakan
didasar tanaman akan berlanjut. Daun bendera dan dua
daun dibawah tetap hijau. Saat gabah mencapai tahap ½
matang, maka akan berubah menjadi gumpalan lunak dan
kemudian mengeras. Gabah akan mulai menguning dan
pelayuan pada dasar tanaman akan tampak jelas. Gabah
yang telah matang penuh akan memiliki tekstur yang
keras dan berwarna kuning (Makarim dan Suhartatik, ,
2009).
Padi yang memiliki umur tanaman pendek ialah padi
IR 64 dengan lama tanam 110-115 hari dimana lama fase
vegetatif 45 hari, fase reproduktif 35 hari dan fase
pematangan 30-35 hari. Hasil panen padi IR 64 bisa
13
mencapai kurang lebih 5 ton/h. Bentuk tanaman padi IR
64 tegak dengan tinggi kurang lebih 85 cm dan memiliki
anakan yang hingga 36 anakan (Sumardi, 2010). Batang
dan kaki padi IR 64 berwarna hijau, sedangkan telinga
daun dan lidah daun tidak berwarna. Posisi daun dan
daun bendera tegak dan daun memiliki permukaan yang
kasar. Gabah yang dihasilkan memiliki bentuk ramping
dan panjang dan berwarna kuning bersih. Bobot 1000
butir benih padi IR 64 ialah 27 gram. (BBPTP, 2008).
B. Cekaman Kekeringan Terhadap Pertumbuhan Tanaman
Kekeringan merupakan cekaman lingkungan yang
menyebabkan tanaman kekurangan air, sehingga berakibat
terganggunya proses-proses fisiologi tanaman yang dapat
ditunjukkan dengan berkurangnya organ-organ itu sendiri
dan selanjutnya berpengaruh terhadap hasil. Tanaman
mengalami cekaman kekeringan bila terjadi kekurangan
air, baik di dalam tanaman maupun di dalam tanah.
Tanaman dapat menghindari kekeringan dengan
mempertahankan serapan air. Mekanisme ini ditunjang
oleh sistem perakaran yang mampu menyerap air tanah
lebih banyak. Terjadinya cekaman air selama masa
pertumbuhan tanaman, umumnya akan mempengaruhi
morfologi, fisiologi dan aktivitas pada tingkat
molekular tanaman padi, seperti tertundanya pembungaan,
mengurangi distribusi dan alokasi bahan kering,
mengurangi kapasitas fotosintesis akibat dari
14
menutupnya stomata dan rusaknya kloroplas. Tanaman yang
toleran terhadap kondisi cekaman kekeringan akan
menunjukkan respons morfologis dan fisiologis yang
berbeda dibandingkan dengan tanaman yang peka. Respons
morfologi dalam beradaptasi terhadap cekaman kekeringan
dapat diketahui melalui sistem perakaran dan bentuk
tajuk. Respon fisiologis terhadap cekaman kekeringan
dapat diketahui melalui perubahan perilaku stomata,
peningkatan akumulasi prolin, fotosintesis, translokasi
dan penurunan potensial osmotik jaringan (Santos,
2009).
Padi merupakan tanaman yang sangat sensitif
terhadap cekaman kekeringan. Menurut Farooq et al (2010),
mekanisme pertahanan tanaman padi terhadap kekeringan
dilakukan dengan cara menutup stomata untuk mengurangi
transpirasi. Cekaman kekeringan akan menurunkan jumlah
daun, luas daun, bobot kering tanaman, jumlah anakan,
tinggi tanaman dan transpirasi. Tanda awal dari
pengaruh kekeringan ialah menggulungnya daun yang
diakibatkan oleh hilangnya turgor pada daun, kemudian
terjadi penutupan stomata dan pengurangan perkembangan
sel dengan demikian akan mengurangi luas permukaan daun
dan laju fotosintesis tiap satuan luas daun. Tanaman
padi yang mengalami cekaman air pada fase-fase
pembungaan dan pengisian biji menyebabkan berkurangnya
komponen-komponen hasil. Pengaruh cekaman air pada masa
15
pembungaan dan pengisian biji akan mempengaruhi banyak
gabah yang hampa akibat kekurangan air. Air berpengaruh
besar terhadap pertumbuhan vegetatif maupun generatif
tanaman padi, terutama dapat mempengaruhi rendahnya
hasil panen. Ketahanan terhadap cekaman air merupakan
sifat yang kompleks dari beberapa karakter morfologi,
fisiologi, dan biokimia yang secara positif
berkontribusi kepada kemampuan untuk tumbuh dan
berproduksi pada keadaan yang terbatas. Mekanisme
fisiologis tanaman padi dalam menghadapi cekaman air
dapat dengan cara menghindar atau toleransi. Peranan
air sangat penting pada saat pembentukan anakan dan
awal fase pemasakan (Sulistyo dkk, 2012).
C. Interaksi Rhizobacteri Dengan Tanaman
Rhizobacteri merupakan bakteri yang tumbuh di sekitar
perakaran tanaman/zona perakaran. Rhizobacteri banyak
dikenal sebagai bakteri pemacu tumbuh tanaman populer
disebut plant growth promoting rhizobacteria (PGPR), yaitu
kelompok bakteri menguntungkan yang mengkolonisasi
rizosfer. Aktivitas Rhizobacteri memberi keuntungan bagi
pertumbuhan tanaman. Pengaruh langsung Rhizobacteri
didasarkan atas kemampuannya menyediakan dan
memobilisasi atau memfasilitasi penyerapan berbagai
unsur hara dalam tanah serta mensintesis dan mengubah
konsentrasi berbagai fitohormon pemacu tumbuh.
16
Sedangkan pengaruh tidak langsung berkaitkan dengan
kemampuan Rhizobacteri menekan aktivitas patogen dengan
cara menghasilkan berbagai senyawa atau metabolit
seperti antibiotik dan siderophore (Husen dan Irawan,
2010). Sebagian besar Rhizobacteri berasal dari kelompok
gram-negatif dengan jumlah strain paling banyak dari
genus Pseudomonas dan beberapa dari genus Serratia.
Selain kedua genus tersebut, dilaporkan antara lain
dari genus Azotobacter, Azospirillum, Acetobacter, Burkholderia dan
Bacillus (Husen dkk. 2011). Meskipun sebagian besar
Bacillus (gram-positif) tidak tergolong pengkoloni akar,
beberapa strain tertentu dari genus ini ada yang mampu
melakukannya, sehingga bisa digolongkan sebagai
Rhizobacteri pemacu tumbuh tanaman.
Fungsi Rhizobacteri dalam meningkatkan pertumbuhan
tanaman dibagi dalam tiga kategori, yaitu: 1)
pemacu/perangsang pertumbuhan (biostimulants) dengan
mensintesis dan mengatur konsentrasi berbagai zat
pengatur tumbuh seperti asam indol asetat (IAA),
Giberellin, Sitokinin, dan Etilen dalam lingkungan
akar; 2) penyedia hara (biofertilizers) dengan menambat N2
dari udara secara asimbiosis dan melarutkan hara P yang
terikat di dalam tanah; 3) pengendali patogen berasal
dari tanah (bioprotectants) dengan cara menghasilkan
berbagai senyawa atau metabolit anti patogen seperti
Siderophore, β-1,3- glukanase, Kitinase, antibiotik, dan
17
Sianida (Husen dkk. 2011). Agung_stuti (2012) menemukan
adanya bakteri yang dapat tumbuh pada rumput yang
bertahan pada daerah terdampak erupsi Merapi. Hasil
isolasi tahun 2013 didapat 4 isolat yang berbeda warna,
diameter dan bentuk. Ke empat isolat tersebut memiliki
kemampuan dalam Nitrifikasi, Amonifikasi dan melarutkan
unsur Phosphat. Pertumbuhan isolat bakteri Rhizobacteri
indigenous Merapi optimal setelah dilakukan kultur gojok
selama 48 jam. Pertumbuhan isolat bakteri Rhizobacteri
indigenous Merapi baru memulai fase penurunan setelah 48
jam dan jumlah bakteri terus menurun sampai waktu 72
jam (Agung_Astuti dkk, 2013).
D. Formulasi Inokulum Padat Rhizobacteri indigenous
Merapi
Formulasi bahan pembawa bertujuan untuk mendapatkan
inokulum dengan komposisi yang sesuai bagi pertumbuhan
mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur selama masa
penyimpanan dan tetap memiliki efektivitas yang baik
saat diaplikasikan sebagai pupuk hayati. Bahan pembawa
inokulum yang lazim disebut sebagai carrier pada dasarnya
merupakan suatu bahan yang dapat digunakan sebagai
tempat hidup inokulum pupuk hayati sebelum
diaplikasikan, sehingga harus dapat mengaktifkan
kegiatan mikrobia agar mampu tumbuh dan berkembang
pada saat digunakan (Puriana, 2007)..
18
Hal yang perlu diperhatikan untuk membuat bahan
pembawa yang baik bagi mikroba ialah: 1) non toksik
terhadap inokulum, 2) memiliki kapasitas absorpsi yang
baik, 3) mudah untuk diproses dan bebas dari bahan yang
dapat membentuk bongkahan, 4) mudah untuk disterilisasi
atau dipasteurisasi, 5) tersedia dalam jumlah yang
banyak, 6) harga tidak mahal, 7) memiliki kapasitas
penyangga yang baik, 8) tidak bersifat toksik terhadap
tanaman dan 9) memiliki sifat perekat bagi benih
(FNCA, 2006; Metting, 1992). Bahan pembawa (carrier) yang
digunakan harus memiliki nutrisi yang dibutuhkan bagi
mikroba seperti air, karbon, energi, nitrogen, elemen
mineral dan faktor pertumbuhan (suhu, pH, aerasi).
Karbon adalah sumber utama dalam sintesa untuk
menghasilkan sel baru dan karbohidrat merupakan sumber
karbon yang mungkin dan paling ekonomis. Bakteri juga
membutuhkan Nitrogen organik dalam bentuk asam amino
tunggal atau material kompleks meliputi asam nukleat
dan vitamin (Puriana, 2007). Kelembaban carrier juga
perlu diperhatikan sekitar 40% atas dasar berat basah
carrier (Metting, 1992).
Sejak lama banyak yang telah meneliti tentang
penggunaan gambut sebagai bahan pembawa mikrobia,
karena dapat menyediakan perlindungan yang lebih baik
untuk Rhizobia di dalam kemasan dan pada benih yang telah
dilapisi oleh bahan pembawa. Inokulum padat dapat
19
berbentuk granular maupun bubuk. Ukuran partikel yang
dibutuhkan untuk menghasilkan inokulum bubuk ialah
antara 60-100 m. Inokulum bubuk biasanya digunakan
langsung untuk melapisi benih sebelum ditanam. Inokulum
bubuk dibuat agar dapat menempel pada benih dengan
pelapisan permukaan benih menggunakan bahan perekat
adhesif yang sesuai sebelum inokulum diaplikasikan,
seperti : sukrosa 10%, gum arabic 10% (w/v), atau metil
selulosa 1%). Pengaplikasian inokulum secara langsung
pada benih akan lebih efektif dan lebih mudah. Aplikasi
inokulum pada benih dapat dilakukan dengan takaran 4-6
g/kg benih atau setara dengan 0,28-0,42 kg/ha
(Metting, 1992). Sudah banyak penelitian yang berhasil
memformulasikan beberapa bahan seperti zeolit, arang
aktif, kaolin, debu vulkanik maupun kapur sebagai bahan
pembawa mikroba dan teruji efektif saat diaplikasikan
dan tetap memberikan viabilitas mikrobia yang baik
selama penyimpanan.
1. Gambut
Gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari
akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk
sehingga kandungan bahan organiknya tinggi. Gambut
terbentuk tatkala bagian-bagian tumbuhan yang luruh
terhambat pembusukannya, biasanya di lahan-lahan
berawa, karena kadar keasaman yang tinggi atau kondisi
anaerob di perairan setempat. Sebagian besar tanah
20
gambut tersusun dari serpih dan kepingan sisa tumbuhan,
daun, ranting, pepagan, bahkan kayu-kayu besar, yang
belum sepenuhnya membusuk (Wikipedia, 2013).
Karakteristik kimia lahan gambut sangat ditentukan oleh
kandungan, ketebalan dan jenis di dasar gambut, serta
tingkat dekomposisi gambut. Kandungan mineral gambut di
Indonesia umumnya kurang dari 5% dan sisanya adalah
bahan organik. Fraksi organik terdiri dari senyawa-
senyawa humat sekitar 10 hingga 20% dan sebagian besar
lainnya adalah senyawa lignin, selulosa, hemiselulosa,
lilin, tannin, resin, suberin, protein, dan senyawa
lainnya. Komposisi kimia gambut sangat dipengaruhi oleh
bahan induk tanamannya, tingkat dekomposisi dan sifat
kimia lingkungan aslinya (Ratmini, 2012).
Tanah gambut umumnya memiliki kesuburan yang
rendah, ditandai dengan pH masam, ketersediaan sejumlah
unsur hara makro (K, Ca, Mg, P) dan mikro (Cu, Zn, Mn,
dan Bo) yang rendah, mengandung asam-asam organik yang
beracun, serta memiliki Kapasitas Tukar Kation (KTK)
yang tinggi tetapi Kejenuhan Basa (KB) rendah.
Kandungan Al pada tanah gambut umumnya rendah sampai
sedang, berkurang dengan menurunnya pH tanah. Kandungan
N total termasuk tinggi, namun umumnya tidak tersedia
bagi tanaman, oleh karena rasio C/N yang tinggi
(Najiyati dkk, 2005). Telah banyak penelitian mengenai
pemanfaatan gambut sebagai bahan pembawa mikrobia,
21
Andhika (2008) telah meneliti bahwa gambut yang
dicampur dengan kaolin (2:1 w:w) dan 2,5% w/w CaCO3
dengan pH 6,46 merupakan formula pupuk hayati terbaik
dengan kepadatan populasi Rhizobacteri IMRG-4, IMRG-5,
IMRG-19, IMRG-30 sebesar 1011,39 CFU/g. Sedang
pemanfaatan gambut sebagai bahan pembawa yang tidak
steril ialah mencampurkan gambut dengan inokulum cair
isolat bakteri kemudian pH disesuaikan hingga 6,5-6,8
menggunakan CaCO3 dan kadar air yang dibutuhkan ialah
40% dari dasar berat basah (Metting, 1992).
2. Arang Aktif
Arang aktif adalah suatu bahan hasil proses
pirolisis arang pada suhu 600-900oC. Selama ini bahan
arang aktif yang digunakan berasal dari limbah limbah
kayu dan bambu. Bahan lainnya yang dapat digunakan
adalah dari limbah pertanian antara lain sekam padi,
jerami padi, tongkol jagung, batang jagung, serabut
kelapa, tempurung kelapa, tandan kosong dan cangkang
kelapa sawit, dan sebagainya. Pada tahap awal limbah
pertanian dibuat arang melalui proses karbonisasi 500oC
dan tahap selanjutnya dilakukan aktivasi pada suhu
800oC-900oC. Perbedaan mendasar arang dengan arang
aktif adalah bentuk pori-porinya. Pori-pori arang aktif
lebih besar dan bercabang serta berbentuk zig-zag. Arang
aktif bersifat multifungsi, selain media meningkatkan
kualitas lingkungan juga pori-porinya sebagai tempat
22
tinggal ideal bagi mikroba termasuk mikroba
pendegradasi sumber pencemar seperti residu pestisida
dan logam berat tertentu (Harsanti dkk, 2011).
Arang aktif memiliki fungsi sebagai rumah untuk
mikroorganisme di dalam tanah. Pori-pori kecil pada
karbon aktif digunakan sebagai tempat tinggal bakteri,
sedangkan pori besar dan retakan (cracks) digunakan
sebagai tempat berkumpul. Penggunaan arang aktif di
lahan sawah dapat meningkatkan jumlah bakteri dan
bakteri fiksasi Nitrogen (Azotobacter) di sekitar akar
tanaman pangan. Arang aktif sering dipergunakan untuk
menstimulir pertumbuhan akar. Hasil penelitian di
Jepang melaporkan bahwa lahan yang diberi arang aktif
meningkatkan frekuensi bakteri fiksasi Nitrogen sebesar
10-15% di Hokkaido dan Tohoku (Honshu Utara), 36-48% di
Kanto hingga Chugoku (Honshu sebelah Timur-Barat), dan
59-66% di Kyusu (Harsanti dkk, 2011).
Pemanfaatan arang pirolisis (Bio-Char) sebagai bahan
pembawa bakteri pemantap agregat (bioamelioran)
Pseudomonas fluorescens PG7II.1, Flavobacterium sp. PG7II.2
dan P. diminuta PG7II.9 dengan masa simpan 3-9 bulan
dapat mempertahankan populasi bakteri lebih tinggi
(10-8CFU/gram) dibandingkan dengan bahan pembawa kompos
dan gambut. Bio-char memiliki kapasitas menahan air
yang cukup tinggi sehingga memungkinkan terjaganya
kelembaban bahan pembawa sehingga menciptakan daya
23
dukung lingkungan untuk perkembangbiakan sel bakteri.
Diketahui bahwa penggunaan bio-char sebagai komponen
bahan pembawa memiliki potensi untuk mempertahankan
daya tumbuh bakteri dalam jangka waktu 12 bulan, serta
mempunyai nilai pH 6,7 dan kadar air 12,2 % (Santi dan
Goenadi, 2010). Komposisi bahan pembawa yang digunakan
dalam penelitian tersebut terdiri dari tiga komponen
yaitu zeolit granul (diameter 1-3 mm), bio-char (80
mesh) dan mineral liat (80 mesh). Zeolit granul
digunakan sebagai inti granulasi, sementara bio-char dan
mineral liat masing-masing digunakan sebagai pelapis
dan pengikat.
3. Kapur
Kapur merupakan bahan ameliorasi atau bahan yang
dapat meningkatkan kesuburan melalui perbaikan kondisi
fisik dan kimia tanah. Bahan amelioran yang baik bagi
lahan gambut memiliki kriteria: memiliki kejenuhan basa
(KB) tinggi, mampu meningkatkan derajat pH secara
nyata, mampu memperbaiki struktur tanah, memiliki
kandungan unsur hara yang banyak atau lengkap sehingga
juga berfungsi sebagai pupuk, mampu mengusir senyawa
beracun, terutama asam-asam organik. Penggunaan kapur
dapat meningkatkan kadar pH tanah dan basa-basa seperti
tanah gambut yang masam (Agus dan Subiksa, 2008).
Menurut Hardjowigeno (1996) kapur yang diberikan ke
dalam tanah gambut akan memperbaiki kondisi tanah
24
gambut dengan cara menaikkan pH tanah, mengusir
senyawa-senyawa organik beracun, meningkatkan KB,
menambah unsur Ca dan Mg, menambah ketersedian hara,
memperbaiki kehidupan mikrooraginisme tanah termasuk
yang berada dalam bintil-bintil akar.
Menurut Wijaya-Adhi (1955) pemberian kapur
merupakan syarat pertama dalam memperbaiki kesuburan
tanah gambut. Hasil penelitian Arsyad (2009) menunjukan
penggunaan kapur Dolomit (CaMg(CO3)2) sebagai carrier
Rhizobium dari bintil akar putri malu dengan
perbandingan 5 g Dolomit berbanding 30 ml starter
kultur Rhizobium yang paling efektif sebagai pupuk pada
pertumbuhan tanaman kacang hijau.
Dolomit berasal dari batu kapur Dolimitik dengan
rumus [CaMg (CO3)2]. Pupuk Dolomit sebenarnya tergolong
mineral primer yang mengandung unsur Ca dan Mg. Pupuk
ini sebenarnya banyak digunakan sebagai bahan pengapur
pada tanah-tanah masam untuk menaikkan pH tanah.
Dolomit banyak digunakan karena relatif murah dan mudah
didapat. Disamping itu bahan tersebut dapat memperbaiki
sifat fisik tanah dan kimia dengan tidak meninggalkan
residu yang merugikan tanah. Apabila pH tanah telah
meningkat, maka kation Aluminium akan mengendap sebagai
gibsit sehingga tidak lagi merugikan. Dolomit terbentuk
dari hasil reaksi antara unsur Mg dengan batu gamping
(limestone). Pembentukan dolomit berlangsung dalam air
25
laut dan unsur Mg yang diperlukan berasal dari hasil
disosiasi (penguraian) garam MgCO3 yang terdapat dalam
air laut. Sebagai mana diketahui bahwa air laut
mengandung berbagai jenis garam-garaman, antara lain
MgCO3 dan CaCO3. Proses pembentukannya berlangsung
ratusan sampai ribuan tahun.
4. Kaolin
Kaolin merupakan masa batuan yang tersusun dari
material lempung dengan kandungan besi yang rendah, dan
umumnya berwarna putih atau agak keputihan. Kaolin
mempunyai komposisi hidrous Alumunium Silikat
(2H2O.Al2O3.2SiO2), dengan disertai beberapa mineral
penyerta. Proses pembentukan kaolin (kaolinisasi) dapat
terjadi melalui proses pelapukan dan proses hidrotermal
alterasi pada batuan beku felspartik, mineral-mineral
potas aluminium silka dan feldspar diubah menjadi
kaolin. Endapan kaolin ada dua macam, yaitu: endapan
residual dan sedimentasi. Mineral yang termasuk dalam
kelompok kaolin adalah kaolinit, nakrit, dikrit, dan
halloysit (Al2(OH)4SiO5.2H2O), yang mempunyai kandungan
air lebih besar dan umumnya membentuk endapan
tersendiri. Sifat-sifat mineral kaolin antara lain,
yaitu: kekerasan 2-2,5, berat jenis 2,6-2,63, plastis,
mempunyai daya hantar panas dan listrik yang rendah,
serta pH bervariasi. Potensi dan cadangan kaolin yang
besar di Indonesia terdapat di Kalimantan Barat,
26
Kalimantan Selatan, dan Pulau Bangka dan Belitung,
serta potensi lainnya tersebar di Pulau Sumatera, Pulau
Jawa, dan Sulawesi Utara (ESDM. 2005).
Hasil penelitian Andhika (2008) mengenai
pemanfaatan gambut yang dicampur dengan kaolin (2:1
w:w) dan 2,5% w/w CaCO3 dengan pH 6,46 merupakan
formula pupuk hayati terbaik dengan kepadatan populasi
Rhizobacteri IMRG-4, IMRG-5, IMRG-19, IMRG-30 sebesar
1011,39 CFU/g.
5. Kulit Pisang
Kandungan nutrisi tertinggi kulit pisang ialah
karbohidrat sekitar 18,5% per 100 gram. Kandungan
karbohidrat yang tinggi pada kulit pisang dapat
dimanfaatkan sebagai bahan pembawa bagi bakteri. Karbon
adalah sumber utama dalam sintesa untuk menghasilkan
sel baru dan karbohidrat merupakan sumber karbon yang
mungkin dan paling ekonomis (Puriana, 2007). Kulit
pisang juga mengandung nutrisi lain seperti : Protein,
Kalsium, Fosfor, Lemak, Vitamin C, Vitamin B dan Besi.
Hasil penelitian Tyas (2008) menunjukan bahwa
pemanfaatan kulit pisang 60-90 g dan zeolit 30-60 g
sebagai carrier dapat mempertahankan populasi bakteri
pelarut pospat Bacillus megatherium hingga minggu ke-6
penyimpanan dengan rata-rata populasi sebesar 5,2x107
CFU/g bahan pembawa.
27
6. Zeolit
Zeolit merupakan kristal alumina silikat yang
terbentuk dari tetrahedral alumina dan silika dengan
rongga-rongga di dalam yang berisi ion-ion logam,
biasanya golongan logam alkali, dan molekul air yang
bergerak bebas. Zeolit merupakan suatu kelompok mineral
yang dihasilkan dari proses hidrotermal pada batuan
beku basa. Mineral zeolit biasanya dijumpai mengisi
celah-celah ataupun rekahan dari batuan tersebut.
Zeolit juga merupakan endapan dari aktivitas vulkanik
yang banyak mengandung unsur silika. Sifat umum zeolit
antara lain mempunyai susunan kristal yang agak lunak,
berat jenis 2-2,4, berwarna kebiruan-kehijauan, putih
dan coklat. Jenis mineral zeolit yang terdapat di
Indonesia adalah modernit dan klipnoptilolit (Eddy,
2006). Secara kimia kandungan zeolit yang utama adalah:
SiO2=62,75%; A12O3=12,71%; K2O=1,28%; CaO=3,39%;
Na2O=1,29 %; MnO=5,58 %; Fe2O3=2,01%; MgO= 0,85 %;
Clinoptilotit =30%; Mordernit = 49%. Sedangkan nilai
KPK antara 80-120 me/100 gr, nilai yang tergolong
tinggi untuk penilaian tingkat kesuburan tanah.
Nilai KPK akan menentukan kemampuan bahan tersebut
untuk menyimpan pupuk yang diberikan sebelum diserap
tanaman. Secara umum fungsi zeolit bagi lahan
pertanian adalah: meningkatkan kadar oksigen terlarut
dalam air irigasi lahan persawahan, menjaga
28
keseimbangan pH tanah, mampu mengikat logam berat yang
bersifat meracun tanaman misalnya Pb dan Cd, mengikat
kation dari unsur dalam pupuk misalnya NH4+dari Urea
dan K+ dari KCl, sehingga penyerapan pupuk menjadi
effisien, ramah lingkungan karena menetralkan unsur
yang mencemari lingkungan, memperbaiki struktur tanah
(sifat fisik) karena kandungan Ca dan Na, meningkatkan
KPK tanah (sifat kimia), meningkatkan hasil tanaman.
Bila dibandingkan dengan bahan organik dalam fungsinya
sebagai pemantap tanah, maka zeolit akan lebih unggul
(Edi, 2004). Hasil penelitian Tyas (2008) menunjukan
bahwa dengan pemanfaatan kulit pisang 60-90 g dan
zeolit 30-60 g sebagai carrier dapat mempertahankan
populasi bakteri pelarut pospat Bacillus megatherium
hingga minggu ke-6 penyimpanan dengan rata-rata
populasi sebesar 5,2x107 CFU/g bahan pembawa.
7. Debu Vulkanik Kelud (DVK)
Debu vulkanik adalah bahan material vulkanik
jatuhan yang disemburkan ke udara saat terjadi suatu
letusan, terdiri dari batuan berukuran besar sampai
berukuran halus. Batuan yang berukuran besar (bongkah -
kerikil) biasanya jatuh disekitar kawah sampai radius 5
– 7 km dari kawah, dan yang berukuran halus dapat jatuh
pada jarak mencapai ratusan km bahkan ribuan km dari
kawah karena dapat terpengaruh oleh adanya hembusan
angin. Kandungan kimia debu vulkanik berbeda-beda untuk
29
tiap gunung berapi (Wikipedia, 2013). Unsur yang paling
berlimpah dalam magma adalah silika (SiO2) dan oksigen.
Letusan erupsi rendah dari basal (batuan beku)
memproduksi karakteristk abu berwarna gelap yang
mengandung 45-55 persen silika yang kaya akan zat besi
(Fe) dan magnesium (Mg). Gas-gas utama dilepaskan
selama aktivitas gunung api adalah air, Karbon
Dioksida, Sulfur Dioksida, Hidrogen, Hidrogen Sulfida,
Karbon Monoksida Dan Hidrogen Klorida. Kandungan
Belerang dan Gas Halogen serta logam ini dihapus dari
atmosfer oleh proses reaksi kimia. Menurut Suradikarta,
abu vulkanik Gunung Kelud Jawa Timur mengandung 45,9%
SiO2 dan mineral yang dominan adalah plagioklas
intermedier. Abu vulkanik Gunung Kelud dapat
meningkatkan pH tanah, meningkatkan tinggi tanaman,
berat kering tanaman dan akar jagung dan semakin halus
abu vulkan semakin efektif terhadap pertumbuhan tanaman
jagung (Suriadikarta dkk, 2010). Hasil Penelitian
Dwiyantores (2012) menunjukan bahwa pemanfaatan Debu
Vulkanik Merapi (DVM) +15% air kelapa (v/b) + 0,1%
bahan perekat (v/b) dapat digunakan sebagai media
memperbanyak bakteri Bacillus thuringiensis dengan kepadatan
populasi 322 x 108 cfu/ml sampel setelah 24 jam setelah
inkubasi.
30
8. Air Kelapa
Air kelapa kaya akan Kalium hingga 17 % , gula
antara 1,7 sampai 2,6 % dan protein 0,07 hingga 0,55 %.
Mineral lainnya antara lain Natrium (Na), Kalsium (Ca),
Magnesium (Mg), Ferum (Fe), Cuprum (Cu), Fosfor (P) dan
Sulfur (S) (Bustamante, 2004). Sedangkan menurut
Dwidjoseputro (1994) disamping kaya mineral, air kelapa
juga mengandung berbagai macam vitamin seperti Asam
Sitrat, Asam Nikotinat, Asam Pantotenal, Asam Folat,
Niacin, Riboflavin, dan Thiamin. Terdapat pula dua
hormon alami yaitu auksin dan sitokinin sebagai
pendukung pembelahan sel embrio kelapa. Penelitian yang
dilakukan oleh Puriana (2007) menunjukan bahwa air
kelapa dapat digunakan sebagai media memperbanyak
bakteri Bacillus thuringiensis Barliner.
9. Gula Merah
Gula merah terbentuk dari hasil karamelisasi air
nira. Setiap 100 g gula merah aren terkandung 368 cal
Kalori, 95 g Karbohidrat, 75 mg Kalsium, 35 mg Fosfor,
3 mg Besi dan 4 mg Air. Gula berfungsi sebagai starter
untuk menstimulir perkembangan mikroba (Husen dan
Irawan, 2010).
E. Bahan Pengemas Inokulum Rhizobacteri
Salah satu tahap dari pembuatan pupuk hayati ialah
pengemasan. Syarat dari bahan kemasan yang akan
31
digunakan sebagai pupuk hayati ialah harus kedap
udara/kedap air, tidak mudah pecah/koyak, bobot kemasan
30- 150 g neto. Bahan kemasan bisa digunakan dari
Alumunium foil atau plastik Polietilen dan kedap cahaya
minimal 40%. Polietilen yang akan digunakan dianjurkan
memiliki ketebalan sekitar 0,038-0,076 mm sehingga
mampu menjaga kelembaban dari pupuk hayati tersebut,
namun kemasan tersebut juga dapat memungkinkan
pertukaran gas yang memadai dan dapat mengontrol dari
adanya kontaminasi. (Metting, 1992).
1. Plastik Polietilen (PE)
Polietilen adalah termoplastik yang digunakan
secara luas oleh konsumen produk sebagai kantong
plastik. PE merupakan polimer yang terdiri dari rantai
panjang monomer etilena. Molekul etena C2H4 adalah
CH2=CH2. Dua grup CH2 bersatu dengan ikatan ganda.
Polietilena dibentuk melalui proses polimerisasi dari
etena. Polietilena bisa diproduksi melalui proses
polimerisasi radikal, polimerisasi adisi anionik,
polimerisasi ion koordinasi, atau polimerisasi adisi
kationik (Wikipedia, 2011).
2. Alumunium Foil
Aluminium foil adalah bahan kemasan berupa lembaran
logam aluminum yang padat dan tipis dengan
ketebalan <0.15 mm. Kemasan ini mempunyai tingkat
32
kekerasan dari 0 yaitu sangat lunak, hingga H-n
yang berarti keras. Semakin tinggi bilangan H-, maka
aluminium foil tersebut semakin keras. Alumunium Foil
memiliki daya rentang yang kuat, tidak mudah sobek.
Aluminium Foil dirancang khusus untuk memantulkan
radiasi panas hingga 95% dan sangat cocok untuk
mencegah penguapan dan menghindari kebocoran (Anonim,
2010).
Hasil penelitian Andhika (2008) menunjukkan bahwa
bahan pembawa (carrier) Gambut + kaolin (2:1 w:w) + 2,5%
w/w CaCO3 dengan pH 6,46 untuk kemasan plastik memiliki
kepadatan populasi Rhizobakteri IMRG-4, IMRG-5, IMRG-
19, IMRG-30 adalah 1011,39 cfu/g. Bahan pembawa (carrier)
gambut + 2,5% w/w CaCO3 dengan pH 6,4 untuk kemasan
alumunium foil memiliki kepadatan populasi Rhizobakteri
IMRG-4, IMRG-5, IMRG-19, IMRG-30 adalah 1011,35 cfu/g.
F. Hipotesis
Formula inokulum padat Rhizobacteri indigenous Merapi
dengan menggunakan carrier gambut + 1 % (w/w) gula +
10% (w/w) arang aktif + 2% (w/w) CaCO3 dalam kemasan
Alumunium foil, merupakan formula terbaik terhadap
aktifitas Rhizobacteri indigenous Merapi dan pertumbuhan
tanaman padi yang mengalami cekaman kekeringan.
III. METODE PENELITIAN
A. Rencana Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret
hingga Juli 2014 bertempat di Laboratorium
Agrobioteknologi, Fakultas Pertanian UMY, Jl. Lingkar
Barat,Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul,
DIY.
B. Bahan dan Alat Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Padi IR 64, Rhizobakteri indigenous Merapi isolat MA, MB,
MD, aquadest, alkohol, gambut, gula jawa, arang aktif,
CaCO3, Kaolin, Zeolit, air kelapa, tepung kulit pisang,
Debu Vulkanik Kelud, gula merah, medium LBA dan LBC,
medium Ekstrak Tanah Agar, plastik polietilen,
Alumunium foil, pupuk kandang, pupuk NPK (Urea, SP-36
dan KCl) dan pestisida.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah
autoklaf, oven, erlemeyer, gelas piala, lampu bunsen,
lumpang, martir, rotary shaker, tabung reaksi, jarum ose,
petridish, driglasky, skalpel, pinset, pipet ukur, mikro
pipet, blue dan yellow tip, colony counter, besek penyemaian,
sungkup, cangkul, penggaris dan timbangan analitik.
33
C. Metode Penelitian
Penelitian dilakukan dalam dua tahap. Tahapan
pertama yaitu pembuatan inokulum campuran Rhizobacteri
indigenous Merapi dan formulasi inokulum padat di
Laboratorium Fakultas Pertanian UMY. Tahap kedua yaitu
aplikasi inokulum padat Rhizobacteri indigenous Merapi pada
benih padi IR 64 serta uji efektifitasnya terhadap
pertumbuhan tanaman padi yang mengalami cekaman.
Percobaan eksperimental pada laboratorium dan lahan
disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan
desain percobaan Faktorial (2X4). Faktor 1 adalah
komposisi bahan pembawa yang terdiri dari 4 aras,
yaitu:
(C1) Gambut + 1 % (w/w) gula + 10% (w/w) arang aktif
+ 2% (w/w) CaCO3
(C2) Gambut + Kaolin (2:1 w:w) + 2,5% (w/w) CaCO3
(C3) Tepung kulit pisang + 40% (w/w) zeolit
34
35
(C4) Debu Vulkanik Kelud + 15% (v/w) air kelapa +
0,1% (v/w) bahan perekat
Faktor 2 adalah jenis bahan pengemas yang terdiri
dari 2 aras, yaitu :
(P1) Plastik polietilen
(P2) Alumunium foil
Total diperoleh 8 kombinasi perlakuan yang masing-
masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali ulangan,
dengan demikian diperoleh 24 unit perlakuan korban
(lampiran 2).
D. Tata Cara Penelitian
1. Tahap Pertama : pembuatan inokulum campuranRhizobacteri indigenous Merapi dan formulasi carier padat
a. Sterilisasi alat dan bahan formula
Alat-alat yang terbuat dari logam dan gelas dicuci
bersih kemudian setelah kering alat-alat tersebut
dibungkus menggunakan kertas payung. Alat-alat dari
logam dan kaca yang telah terbungkus kertas payung
kemudian disterilkan dalam autoklaf dengan temperatur
121oC bertekanan 1 atm selama 30 menit.
Seluruh bahan formula, seperti tanah gambut, CaCO3,
Aranf aktif, Zeolit, Kaolin, Debu Vulkanik Kelud
dikeringkan anginkan dan kemudian disaring dengan
saringan 30 mesh. Bahan-bahan untuk formulasi perlu
disterilisasi terlebih dahulu dengan menggunakan
autoklav sebanyak dua kali sterilisasi pada 121ºC, 1
36
atm, selama 15-20 menit. pH seluruh bahan dicek dan
disesuaikan hingga didapatkan pH netral 6,5-7.
Kapasitas lapang tanah gambut dapat ditentukan dengan
mengeringkan 50 g tanah pada suhu 80ºC selama 24 jam.
Setelah diautoklaf dan didinginkan, sampel tanah
tersebut dilembabkan dengan akuades steril untuk
mencapai kapasitas lapang.
b. Pembuatan medium LBA untuk identifikasi sertapemurnian isolat Rhizobacteri indigenous Merapi
Medium perbanyakan yang digunakan untuk pembuatan
biakan murni ialah media Luria Bertani Agar (LBA)
(Lampiran 3). Seluruh bahan LBA dimasukkan ke dalam
erlenmeyer kemudian dicampur dengan air dan dipanaskan
hingga larutan mendidih. Larutan LBA yang telah homogen
setelah dipanaskan kemudian diukur kadar pHnya. pH
larutan tidak boleh melebihi 7,2 ataupun kurang dari
6,5. Penyimpangan pH yang terjadi saat pertumbuhan
bakteri di dalam medium akan memperngaruhi protein
(enzim dan sistem transport) yang terdapat pada membran
sel. Struktur protein akan berubah bila pH dalam medium
berubah. pH medium yang menyimpang akan menghambat
pertumbuhan isolat Rhizobacter indigenous Merapi. Medium
LBA kemudian dimasukkan ke dalam 4 tabung reaksi steril
sebanyak 10 ml/tabung, kemudian sebagian medium LBA
dimasukkan ke dalam erlenmeyer. Setelah medium dipindah
ke dalam tabung reaksi dan erlenmeyer, kemudian
37
disterilkan menggunakan autoklaf pada temperatur 121oC
tekanan 1 atm selama 15-20 menit. Medium steril dalam
tabung rekasikemudian diletakan dengan kemiringan 30-
45o. Saat tabung reaksi dimiringkan, media agar tidak
boleh menyentuh tutup tabung untuk menghindari
kebocoran medium dan kontaminasi.
c. Pembuatan Medium LBC untuk perbanyakan isolatRhizobacteri indigenous Merapi
Medium Luria Bertani Cair (LBC) digunakan untuk
pebanyakan Rhizobacteri indigenous Merapi sesuai kebutuhan
(lampiran 3). Seluruh bahan untuk membuat medium LBC
dilarutkan dengan air di dalam erlenmeyer sebanyak 360
ml kemudian dipanaskan hingga mendidih agar seluruh
bahan larut dengan air. Setelah seluruh bahan homogen,
kemudian dilakukan pengecekan pH menggunakan kertas
lakmus. pH yang dikehendaki ialah antara 6,5-7,2.
Medium yang telah siap kemudian disterilkan menggunakan
autoklaf pada temperatur 121oC tekanan 1 atm selama 15-
20 menit. Medium LBA steril kemudian dimasukkan ke
dalam erlenmeyer.
d. Identifikasi koloni dan sel isolat MA, MB dan MDRhizobacter indigenous Merapi
Identifikasi koloni dilakukan dengan cara
menumbuhkan isolat MA, MB dan MD dari hasil pembiakan
kultur murni pada medium LBA menggunakan metode
38
permukaan (surface platting method). Pada tahap ini yang
perlu diamati ialah warna, diameter, bentuk koloni,
bentuk tepi, elevasi dan struktur dalam koloni serta
bentuk dan sifat sel Rhizobacteri indigenous (Lay, 1994).
e. Pembuatan biakan murni Isolat Rhizobacter indigenousMerapi untuk kultur stok
Biakan murni bakteri ialah biakan yang mengandung
satu macam bakteri dan dapat dibiakan menggunakan
bahan cair atau padat (Lay, 1994). Hasil penelitian
yang dilakukan oleh Agung_Astuti (2013) didapat 4
isolat Rhizobacteri indigenous Merapi yaitu MA, MB, MC dan
MD. Ke empat isolat memiliki kemampuan melarutkan
Phospat, Nitrifikasi dan Amonifikasi dan tidak mampu
memfiksasi N, akan tetapi isolat MA, MB dan MD memiliki
kemampuan melarutkan Phospat, Nitrifikasi dan
Amonifikasi yang paling baik dibandingkan dengan isolat
MC, sehingga dalam penelitian akan digunakan 3 isolat
yaitu MA, MB dan MD. Biakan murni akan dibuat dari
isolat MA, MB dan MD pada medium Luria Bertani Agar
miring.
Masing-masing isolat Rhizobacteri indigenous Merapi
dimurnikan dengan cara mengambil 1 ose isolat bakteri
kemudian ditumbuhkan pada medium LBA miring dan
diinkubasi selama 48 jam. Biakan murni haruslah
diinkubasi pada ruangan dengan suhu dan kelembaban yang
sesuai untuk pertumbuhan bakteri yaitu 27oC. Rhizobacter
39
sp. merupakan bakteri mesofil sehingga dapat tumbuh
optimal pada suhu 20-50oC.
f. Perbanyakan dan pembuata starter campuran isolatMA, MB dan MD
Perbanyakan isolat MA, MB dan MD didapat dari
kultur stok isolat MA, MB dan MD. Perbanyakan dilakukan
dengan mengambil 1 ose biakan murni isolat kemudian
diinokulaikan ke dalam tabung reaksi berisi 10 ml
medium LBC untuk tiap isolat, kemudian diinkubasi
dengan suhu ruang 27oC selama 48 jam pada rotary shaker
dengan kecepatan 120 rpm.
Isolat MA, MB dan MD yang telah diperbanyak dan
diinkubasi selama 48 jam kemudian diinokulasikan dan
dicampur sebanyak 10% per isolat ke dalam 4 erlenmeyer
steril berisi 100 ml LBC untuk masing-masing formula.
Proses pengaktifan dilakukan dengan inkubasi pada
rotary shaker selama 48 jam dengan suhu ruang sebagai
fase mid log dari pertumbuhan bakteri. Kultur yang telah
aktif inilah yang akan menjadi inokulum kemudian
diamati viabilitas Rhizobacteri indigenous Merapi pada per
ml dengan metode Total Plate Count pada media Ekstrak
Tanah Agar.
g. Formulasi inokulum padat
Bakteri Rhizobacteri indigenous Merapi diaplikasikan
dengan ketentuan setiap 15 ml starter campuran untuk 50
40
gram bahan pembawa sesuai komposisi yang telah dibuat
(Noviana dkk, 2009). Kemasaman dan kadar air formula
harus disesuaikan yaitu pH 7 dan kadar air 40% untuk
menunjang pertumbuhan Rhizobacteri indigenous Merapi dalam
carrier.
Berikut merupakan komposisi carrier dan penggunaan
bahan kemasan:
1) Gambut + 1 % (w/w) gula + 10% (w/w) arang aktif +
2% (w/w) CaCO3 pada kemasan plastik polietilen
2) Gambut + 1 % (w/w) gula + 10% (w/w) arang aktif +
2% (w/w) CaCO3 pada kemasan alumunium foil
3) Gambut + Kaolin (2:1 w:w) + 2,5% (w/w) CaCO3 pada
kemasan plastik polietilen
4) Gambut + Kaolin (2:1 w:w) + 2,5% (w/w) CaCO3 pada
kemasan alumunium foil
5) Tepung kulit pisang + 40% (w/w) Zeolit pada kemasan
plastik polietilen
6) Tepung kulit pisang + 40% (w/w) Zeolit pada kemasan
alumunium foil
7) Debu Vulkanik + 15% (v/w) air kelapa + 0,1% (v/w)
bahan perekat pada kemasan plastik polietilen
8) Debu Vulkanik + 15% (v/w) air kelapa + 0,1% (v/w)
bahan perekat pada kemasan alumunium foil.
Ke-8 kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali
sehingga didapat 24 unit perlakuan atau 24 kemasan
formula inokulum padat. Penyimpanan formula dilakukan
41
pada ruangan dengan suhu ruang 27oC selama 1 bulan dan
pada minggu ke 1,2,3 dan 4 setelah penyimpanan
dilakukan pengujian viabilitas Rhizobacteri indigenous Merapi
menggunakan metode total palte count pada media Ekstrak
Tanah Agar.
2. Tahap Kedua : aplikasi inokulum padat Rhizobacteriindigenous Merapi pada benih padi IR 64 serta ujiefektifitasnya terhadap pertumbuhan tanaman padiyang mengalami cekaman
a. Persiapan Lahan
Persiapan lahan dilakukan satu minggu sebelum tanam
dengan pembajakan 2 kali. Pembajakan pertama tanpa
garu, kemudian lahan dibagi sesuai lay out pada masing-
masing blok (lampiran 1). Selanjutnya pemberian pupuk
dasar berupa pupuk kandang dan SP-36 sesuai anjuran
pemupukan (lampiran 7).
b. Seleksi benih dengan larutan garam
Seleksi benih dilakukan dengan cara memasukkan
benih ke dalam wadah yang berisi air dan dicampur
dengan garam ± 20% dari volume air yang digunakan,
kemudian benih tersebut diaduk sampai benih terpisah
antara yang terapung dan tenggelam. Benih yang
tenggelam adalah benih yang bagus untuk dibibitkan.
Selanjutnya benih tenggelam diambil dan dibilas dengan
air biasa sampai bersih dan dikering anginkan.
42
c. Uji daya kecambah
Uji daya kecambah dilakukan untuk mengetahui
potensi benih yang bisa berkecambah dari suatu kelompok
atau satuan berat benih. Pengujian ini dilakukan dengan
cara mengambil 100 biji secara acak kemudian benih
disemai pada petridish yang sudah diberi kapas atau
kertas saring yang telah dibasahi. Kemudian dihitung
berapa jumlah benih yang berkecambah, rumus perhitungan
daya kecambah :
DB = (JBK / JBT) x
100 %
Keterangan :
DB = Persentase biji berkecambah
JBK = Jumlah biji berkecambah
JBT = Jumlah biji yang ditabur
d. Aplikasi formula inokulum padat Rhizobacteri padabenih
Berbagai formula Rhizobacteri diaplikasikan pada benih
padi IR 64 sesuai perlakuan dengan takaran 4-6 g/kg
benih atau setara dengan 0,28-0,42 kg/ha (Metting,
1992). Perekatan carrier pada benih dilakukan dengan
membasahi benih padi IR 64 kemudian digunakan bahan
perekat sebagai adhesiv dapat berupa indostik dengan
penggunaan sebanyak 0,03% (v/w). Benih yang telah
terlapisi dengan carrier Rhizobacteri kemudian didiamkan
43
selama 24 dimaksudkan agar Rhizobacteri indigenous Merapi
melekat pada benih.
e. Penyemaian
Setelah 1 hari diinkubasi, bibit diangkat kemudia
ditaburkan diatas 24 besek sesuai perlakuan. Media
tanam berupa tanah Regosol dengan campuran pupuk
kandang 2:1. Besek diletakkan ditempat yang terkena
sinar matahari langsung selama 3 minggu. Benih yang di
semaikan dipelihara dengan cara disiram agar media
tempat persemaian selalu lembab. Selama persemaian
dilakukan pengamatan terhadap pertumbuhan Rhizobacteri
saat fase persemaian. Pengamatan viabilitas Rhizobacteri
indigenous Merapi dilakukan setiap 1 minggu sekali selama
3 minggu dengan metode Total Plate Count menggunakan media
Ekstrak Tanah Agar.
f. Penanaman
Penanaman dilakukan saat padi berumur 3 minggu
setelah semai kemudian ditanam dengan cara tanam 2
bibit dalam 1 lubang untuk mengurangi resiko jika ada
tanaman yang mati. Penanaman dilakukan dengan jarak
tanam 20cm x 20cm (Lampiran 1).
g. Pemeliharaan
1) Pengairan
44
Pada awal penanaman selama 1 minggu kondisi tanah
akan disamakan sesuai syarat penanaman padi sawah yaitu
tergenang, setelah itu pengairan disesuaikan dengan
cekaman kekeringan, jika kadar air melebihi 12% maka
tidak dilakukan penyiraman (lampiran 8). Hasil
penelitian sebelumya mengenai frekuensi penyiraman
tanaman padi yang diinokulasikan Rhizobacteri indigenous
Merapi membuktikan bahwa tanaman padi yang
diinokulasikan dengan Rhizobacteri indigenous Merapi dengan
frekuensi penyiraman 6 hari tidak berbeda nyata dengan
perlakukan tanaman padi tanpa inokulasi dengan
frekuensi penyiraman 1 hari (Agung_Astuti dkk, 2013).
2) Pemupukan susulan
Pupuk susulan di aplikasikan saat 14, 30, 40 hari
setelah tanam dengan menggunakan ½ anjuran penggunaan
Urea. Total kebutuhan pupuk yang digunakan dalam
penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 7.
3) Penyiangan
Penyiangan gulma dilakukan dengan cara mencabut
dan membenamkan gulma ke tanah dengan alat gosrok,
penyiangan dilakukan ketika gulma yang tumbuh di lahan
populasinya > 50% setiap 1 minggu..
4) Pengendalian hama dan penyakit
Pengendalian hama dilakukan secara mekanis, tapi
apabila serangan hama melewati ambang batas akan
45
dilakukan pengendalian secara kimiawi menggunakan
pestisida. Beberapa hama yang sering ada pada tanaman
padi:
i. Wereng Coklat (Nilaparvata lugens)
Hama ini dapat menyebabkan tanaman padi mati kering
dan tampak seperti terbakar atau puso, serta dapat
menularkan beberapa jenis penyakit. Gejala serangan
adalah terdapatnya imago wereng coklat pada tanaman dan
menghisap cairan tanaman pada pangkal batang, kemudian
tanaman menjadi menguning dan mengering. Pengendalian
dianjurkan menggunakan insektisida sistemik Winder 100EC
(0,25-0,5 ml/L), Winder 25WP (0,125-0,5 g/L), WinGran0,5GR ditaburkan merata.
ii. Wereng Hijau (Nephotettix virescens)
Hama wereng hijau merupakan hama penyebar (vector)
virus tungro yang menyebabkan penyakit tungro. Fase
pertumbuhan padi yang rentan serangan wereng hijau
adalah saat fase persemaian sampai pembentukan anakan
maksimum, yaitu umur ± 30 hari setelah tanam. Gejala
kerusakan yang ditimbulkan adalah tanaman kerdil,
anakan berkurang, daun berubah menjadi kuning sampai
kuning oranye. Pencegahan dan pengendalian Pengendalian
dianjurkan menggunakan insektisida sistemik Winder100EC (0,25-0,5 ml/L), Winder 25WP (0,125-0,5 g/L),WinGran 0,5GR ditaburkan merata.
46
iii. Walang Sangit (Leptocorixa acuta)
Walang sangit merupakan hama yang menghisap cairan
bulir pada fase masak susu. Kerusakan yang ditimbulkan
walang sangit menyebabkan beras berubah warna, mengapur
serta hampa. Hal ini dikarenakan walang sangit
menghisap cairan dalam bulir padi. Fase tanaman padi
yang rentan terserang hama walang sangit adalah saat
tanaman padi mulai keluar malai sampai fase masak susu.
Pengendalian dianjurkan dilakukan pada saat gabah masak
susu pada umur 70-80 hari setelah tanam dengan
disemprot insektisida Greta 500EC (1-2 ml/L).
h. Pengamatan dan Pemanenan
Pengamatan dilakukan mulai dari 1 minggu hingga
minggu ke 8 setelah padi ditanam. Panen dilakukan
setelah tanaman berumur 56 hari setelah tanam dengan
ciri tanaman malai berwarna hijau segar.
E. Variabel pengamatan
1. Tahap 1 : Formulasi dan Kemasan inokulum padatRhizobacteri indigenous Merapi
a. Viabilitas bakteri selama penyimpanan
(cfu/ml)
Pengujian dilakukan pada hari ke 7, 14, 21 hari
setelah carrier diformulasikan, dengan menggunakan medium
Ekstrak Tanah Agar dengan kadar NaCl 0,2 M.. 1 gram
sampel carrier diencerkan pada 3 botol air steril 99 ml
47
(10-2; 10-4; 10-6) dan 2 tabung rekasi (10-7;10-8),
sehingga didapat seri pengencerah hingga 10-8. Setiap
0,1 ml pada seri 10-6;10-7;10-8 diinokulasikan dengan
metode permukaan atau surface platting method dan setiap
seri pengenceran yang diujikan (10-7;10-8;10-9) dibuat
ulangan sebanyak 3 kali ulangan. Uji kemampuan hidup
mikroba berdasarkan daya viabilitas dan jumlah koloni
populasi bakteri. Penghitungan populasi bakteri ini
dengan metode Total Plate Count (TPC). Jumlah bakteri per
ml dapat ditentukan dengan menghitung koloni yang
tumbuh dari masing-masing pengenceran. Penentuan jumlah
bakteri per mililiter dengan menggunakan rumus :
Jumlah bakteri per ml sampel (CFU/ml) =Jumlah koloni
Faktor pengenceran
Dalam perhitungan dengan menggunakan cara TPC harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
i. Jumlah koloni tiap cawan petri antara 30-300
koloni.
ii. Tidak ada koloni yang menutup lebih besar dari
setengah luas cawan petri (Spreader).
iii. Perbandingan jumlah koloni dari pengenceran yang
berturut-turut antara pengenceran yang lebih besar
dengan pengenceran sebelumnya. Jika sama atau lebih
kecil dari 2 maka hasilnya dirata-rata, dan jika
lebih besar dari 2 maka yang dipakai adalah jumlah
koloni dari hasil pengenceran sebelumnya.
48
iv. Jika dengan ulangan setelah memenuhi syarat
hasilnya dirata-rata.
2. Tahap 2 : Pertumbuhan Tanaman
a. Viabilitas bakteri selama pembibitan dan
penananam di lahan (cfu/ml)
Pengujian dilakukan pada minggu ke 1, 2 dan 3
selama pembibitan, dengan menggunakan medium Ekstrak
Tanah Agar dengan kadar NaCl 0,2 M.. 1 gram sampel
carrier diencerkan pada 3 botol air steril 99 ml (10-2;
10-4; 10-6) dan 2 tabung rekasi (10-7;10-8), sehingga
didapat seri pengencerah hingga 10-8. Setiap 0,1 ml
pada seri 10-6;10-7;10-8 diinokulasikan dengan metode
permukaan atau surface platting method dan setiap seri
pengenceran yang diujikan (10-7;10-8;10-9) dibuat ulangan
sebanyak 3 kali ulangan. Uji kemampuan hidup mikroba
berdasarkan daya viabilitas dan jumlah koloni populasi
bakteri. Penghitungan populasi bakteri ini dengan
metode Total Plate Count (TPC). Jumlah bakteri per ml
dapat ditentukan dengan menghitung koloni yang tumbuh
dari masing-masing pengenceran.
b. Tinggi tanaman (cm)
Pengukuran tinggi tanaman dilakukan pada tanaman
sampel pada tiap petak. Tinggi tanaman diukur dari
pangkal batang/permukaan tanah sampai ujung daun
teratas menggunakan meteran. Pengamatan dilakuan setiap
minggu hingga minggu ke-8.
49
c. Jumlah anakan
Pengamatan jumlah anakan dilakukan pada tanaman
sampel. Pengamatan dilakukan dengan menghitung
keseluruhan jumlah anakan dinyatakan dalam satuan.
Diamati setiap satu minggu sekali sampai minggu ke-8.
d. Proliferasi akar
Poliferasi akar diketahui dengan melihat penyebaran
perakaran tanaman korban yang diambil setiap 2 minggu
sekali. Pengamatan poliferasi akar dilakukan setiap 2
minggu sekali yaitu pada minggu ke-2, k-4 dan ke-6.
e. Bobot segar dan kering tajuk (g)
Pengamatan bobot segar tajuk dilakukan dengan cara
mencabut tanaman korban kemudian menimbang bagian daun
dan batang. Tajuk ditimbang menggunakan timbangan
analitik, dan dinyatakan dalam satuan gram. Selanjutnya
tajuk dijemur di bawah sinar matahari selama 24 jam dan
dioven pada suhu 60oC sampai bobotnya konstan.
Pengamatan bobot kering tajuk dilakukan dengan cara
menimbang daun dan batang yang sudah kering oven
menggunakan timbangan analitik dan dinyatakan dalam
satuan gram. Penghitungan bobot segar dan kering tajuk
dilakukan setiap 2 minggu sekali yaitu pada minggu ke-
2, k-4 dan ke-6.
f. Bobot segar dan kering akar (g)
Pengamatan bobot segar akar dilakukan dengan cara
mencabut tanaman korban, kemudian menimbang bagian
50
akar yang sudah dibersihkan dari tanahnya. Akar
ditimbang menggunakan timbangan analitik, dan
dinyatakan dalam satuan gram. Selanjutnya akar dijemur
di bawah sinar matahari selama 24 jam dan dioven pada
suhu 60oC sampai bobotnya konstan. Pengamatan bobot
kering akar dilakukan dengan cara menimbang akar yang
sudah kering oven menggunakan timbangan analitik dan
dinyatakan dalam satuan gram. Penghitungan bobot segar
dan kering akar dilakukan setiap 2 minggu sekali yaitu
pada minggu ke-2, k-4 dan ke-6.
g. Bobot segar dan kering tanaman (g)
Pengamatan bobot segar tanaman dilakukan dengan
cara mencabut tanaman sampel kemudian menimbang bagian
seluruh bagian tanaman menggunakan timbangan analitik,
dan dinyatakan dalam satuan gram. Selanjutnya tanaman
dijemur di bawah sinar matahari selama 24 jam dan
dioven pada suhu 60oC sampai bobotnya konstan.
Pengamatan bobot kering tanaman dilakukan dengan cara
menimbang seluruh bagian tanaman yang sudah kering oven
menggunakan timbangan analitik dan dinyatakan dalam
satuan gram.
F. Analisis Data
Data hasil pengamatan setiap hari (kontinyu) dari
semua variabel dibuat grafik untuk mengetahui aktivitas
sakarifikasi dan fermentasi. Data hasil pengamatan
51
dianalisis dengan sidik ragam pada taraf kesalahan 5%
untuk mengetahui pengaruh perlakuan. Jika ada beda
nyata antar perlakuan maka dilakukan uji lanjut dengan
menggunakan uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test).
52
G. Jadwal Penelitian
No KegiatanBlnke-1
Blnke-2
Blnke-3
Blnke-4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 Sterilisasi alat
2 Pembuatan media LBCdan LBA
3Identifikasi kolonidan sel Rhizobacteri
indigenous Merapi
4 Pembuatan biakanmurni
5 Perbanyakan isolatMA, MB dan MD
6 Pembuatan inokulumcampuran
7Formulasi Inokulumpadat Rhizobacteriindigenous Merapi
8Pengamatan 1 (Ujiviabilitas, pH dan
kadar air)
9Pengamatan 2 (Ujiviabilitas, pH dan
kadar air)
10 Seleksi benih danuji daya kecambah
11Pengamatan 3 (Ujiviabilitas, pH dan
kadar air)
12Aplikasi inokulumpadat pada benih
padi IR 6413 Penyemaian
14 Uji viabilitasbakteri 1
15 Uji viabilitas
53
bakteri 2
16 Uji viabilitasbakteri 3
17 Pengolahan lahan18 Penanaman19 Penyiraman20 Penyiangan21 Pengamatan22 Pemanenan23 Analisis data
54
DAFTAR PUSTAKA
Agung-Astuti. 2012. Isolasi dan Karakterisasi Rhizobacteri Akar Rumput di lahan Pasir Vulkanik Merapi . Laporan Penelitian. Tidak dipublikasikan.
Agung-Astuti. Sarjiyah. Haryono. 2013. Uji PotensiRhizobacteri Indigenous Lahan Pasir VulkanikMerapi Untuk Dikembangkan Sebagai Pupuk HayatiDi Lahan Marginal. Prosiding Seminar NasionalPemanfaatan Lahan Marginal Sumberdaya Lokal.
Agung-Astuti. Sarjiyah. Haryono. 2013. PengembanganIsolat Rhizobacteri Indigenous Sebagai PupukHayati Di Untuk Meningkatkan Produktivitas PdiLahan Kering. Laporan Hibah Dikti. Belumdipublikasikan.
Agus, F dan Subiksa, I. 2008. Lahan Gambut: Potensiuntuk Pertanian dan Aspek Lingkungan. BalaiPenelitian Tanah Badan Penelitian dan BalaiPenelitian Tanah dan World Agroforestry Centre(ICRAF), Bogor, Indonesia.
Andhika, S. D. 2008. Produksi Inokulum Dan FormulasiRhizobacteri Tahan Kekeringan Dan Kemasaman SebagaiPupuk Hayati (Biofertilizer). http://www.student-research.umm.ac.id. Diakses pada 09 Pebruari 2014.
Anonim. 2010. Teknologi Pengemasan-Kemasan Logam.http://ocw.usu.ac.id/course/. Diakses pada 13Maret 2014.
Arsyad, M. 2009. Studi Isolasi Rhizobium YangDiinokulasikan Ke Dakam Dolomit Sebagai Pembawa(carrier) Serta Pemanfaatannya Sebagai PupukMikroba. Skripsi S1.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2010. Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap.
55
http://www. Bappenas.go.id. Diakses pada 09 Pebruari 2014.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2000. Sistim Informasi Manajemen Pembangunan di Perdesaan. http://www.ristek.go.id. Diakses pada tanggal 09 Pebruari 2014.
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPTP). 2008. Deskripsi Padi Varietas IR64. http://www.pustaka-deptan.go.id. Diakses pada tanggal 09 Pebruari 2014.
BPS. 2012. Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Provinsi http://www.bps.go.id /tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=2. Diakses pada tanggal 21 Juni 2013.
Bustamante, J. O. 2004. New biotechnologicalapplications of coconuts.Electronic Journal ofBiotechnology. 7 (1) : `1-4.
Dirjen PLA. 2005. Strategi dan Kebijakan PengelolaanLahan. http://www.pertanian.go.id. Dalam Iqbal, Mdan Sumaryanto. 2007. Strategi Pengendalian AlihFungsi Lahan Bertumpu Pada PartisipasiMasyarakat. Analisis Kebijakan Pertanian.5 (2):167-182 Diakses pada tanggal 21 Pebruari 2014.
Dwiyantores. Agung-Astuti dan Supriyadi. 2012.Pengembangan B. thuringiensis Dalam Media PupukOrganik Cair dan Debu Vulkanik Merapi Serta UjiToksinitas Terhadap Ulat Grayak (Spodoptera litura)Pada Tanaman Caisim (Brassica juncea. L). Skripsi S1.Tidak dipublikasikan.
Edi. 2004. “Zeolit Bahan Pembenah Tanah”. Suara Merdeka, 23 Pebruari 2004.
Eddy, R. H. 2006. Potensi Dan Pemanfaatan Zeolit Di Provinsi Jawa Barat Dan Banten. Buletin Sumber Daya Geologi. 1 (2) : 7-12
56
ESDM. 2005. Kaolin. http://www.tekmira.esdm.go.id/data/Kaolin/ulasan.asp ?xdir= Kaolin&commId=19&comm=Kaolin. Diakses pada tanggal 13 Maret 2014.
Farooq, M. Kobayashi, N. Ito, O. Wahid, A dan Serraj, R.2010. Broader leaves result in better performanceof indica rice under drought stress.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20392520.Diakses pada tanggal 15 Maret 2014.
Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA). 2006. Biofertilizer Manual. Japan Atomic Industrial Forum (JAIF). 124 p.
Hardjowigeno, S. 1996. Pengembangan lahan gambut untukpertanian: suatu peluang dan tantangan. BahanOrasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Tanah dalamNajiyati, S. Muslihat, L dan Suryadiputra, I.N. 2005. PANDUAN Pengelolaan Lahan Gambut untukPertanian Berkelanjutan. Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Terbitan (KDT). Bogor: WetlandsInternational – IP.
Harsanti, E.S. dan Ardiwinata, A. N. 2011. Arang Aktif Meningkatkan Kualitas Lingkungan. Badan Litbang. Agroinovasi. XLI (3400) : 2-6
Husen, E. Saraswati, R. dan Hastuti, R. D. 2011.Rizobakteri Pemacu Tumbuh Tanaman.http://www.ristek.go.id.. Diakses pada tanggal 09Pebruari 2014.
Husen, E. dan Irawan. 2010. Efektivitas Dan EfisiensiMikroba Dekomposer Komersial Dan Lokal DalamPembuatan Kompos Jerami.http://balittanah.litbang.deptan.go.id. Diakses padatanggal 09 Pebruari 2014.
Lay, B. W. 1994. Analisis Mikrobia Di Laboratorium. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 34.
57
Makarim, A. K dan Suhartatik, E. Morfologi danFisiologi Tanaman Padi.http://www.litbang.deptan.go.id/special/padi/bbpadi_2009_itkp_11. Diakses tanggal 12Pebruari 2014.
Metting, F. B. Jr.1992. Soil Mikrobial Ecology:Application in agricultural and enviromentalmanagement. Marcel Dekker, Inc. New York. 30-38p.
Najiyati, S., Lili Muslihat dan I Nyoman N.Suryadiputra. 2005. Panduan pengelolaan lahangambut untuk pertanian berkelanjutan. ProyekClimate Change, Forests and Peatlands inIndonesia. Wetlands International – IndonesiaProgramme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor.Indonesia. Hal 20.
Noviana, L dan Raharjo, B. 2009. Viabilitas Rhizobakteri Bacillus sp. DUCC-BR K1.3 pada Media Pembawa Tanah Gambut Disubstitusi dengan Padatan Limbah Cair Industri Rokok. BIOMA. 11 (1) : 30-39
Nurhayati. 2008. Tanggapan Tanaman Kedelai Di TanahGambut Terhadap Pemberian Beberapa Jenis BahanPerbaikan Tanah. Tesis S2.http://www. repository.usu.ac.id . Diakses padatanggal 09 Pebruari 2014.
Puriana, M dan Fardedi. 2007. Pemanfaatan Air KelapaDan Air Rendaman Kedelai Sebagai MediaPerbanyakan Bakteri Bacillus Thuringiensis Barliner.Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia. 9 (1): 64-70.
Ratmini, S. 2012. Karakteristik dan Pengelolaan LahanGambut untuk Pengembangan Pertanian. Jurnal LahanSuboptimal. 1 (2) : 197-206.
58
Santi, L. K dan Goenadi, D. H. 2010. Pemanfaatan bio-char sebagai pembawa mikroba untuk pemantapagregat tanah Ultisol dari Taman Bogo-Lampung.Menara Perkebunan. 78(2), 52-60.
Sumardi. 2010. Produktivitas Padi Sawah Pada KepadatanPopulasi Berbeda. Jurnal ilmu-ilmu pertanianIndonesia. 12 (1): 49-54.
Santos, J. D. 2009. Pengaruh cekaman air terhadapproduktivitas dan total produksi padi sawah diTimor Leste selama 5 tahun (2005, 2006, 2007,2008, 2009).http://maf.gov.tl/uploads/planu_jornal_sientifiku.pdf. Diakses tanggal 12 Maret 2014.
Sulistyo, E. Suwarno. Lubis, I dan Suhendar, D. 2012.Pengaruh Frekuensi Irigasi Terhadap PertumbuhanDan Produksi Lima Galur Padi Sawah. AgroVigor. 5(1) : 2.
Suriadikarta, D.A., Abdullah Abbas Id., Sutono, DediErfandi, Edi Santoso dan A. Kasno. 2010.Identifikasi Sifat Kimia Abu Volkan, Tanah DanAir Di Lokasi Dampak Letusan Gunung Merapi.http://balittanah.litbang.deptan.go.id. Diakses padatanggal 09 Pebruari 2014.
Suratin, A. 1999. Pertumbuhan Padi Gogo Pada TanahRegosol (Entisol) Yang Diinokulasikan DenganRhizobakteri Osmotoleran Pada Kondisi CekamanKekeringan. Tidak Dipublikasikan.
Tyas, I. N. 2008. Pemanfaatan Kulit Pisang SebagaiBahan Pembawa Inokulum Bakteri Pelarut Fosfat.http://www. eprints.uns.ac.id . Diakses pada tanggal09 Pebruari 2014.
Wahyunto, 2005. Lahan sawah rawan kekeringan dankebanjiran di Indonesia. Balai Besar SumberdayaLahan Pertanian. Bogor dalam Bappenas. 2010.Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap.
59
Wikipedia. 2011. Polietilena. http://id.wikipedia.org/wiki/Polietilena. Diakses pada tanggal 15 Maret 2014.
Wikipedia. 2013. Gambut. http://id.wikipedia.org/wiki/Gambut. Diakses pada tanggal 21 Juni 2013.
Wikipedia. 2013. Abu Vulkanik. http://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Vulkanik. Diakses pada tanggal 10 Maret 2014.
Wijaya-Adhi. 1955. Pengelolaan, pemanfaatan danpengembangan rawa untuk usaha tani dalampembangunan berkelanjutan dan berwawasanlingkungan. dalam Najiyati, S. Muslihat, L danSuryadiputra, I. N. 2005. PANDUAN PengelolaanLahan Gambut untuk Pertanian Berkelanjutan.Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan(KDT). Bogor: Wetlands International – IP.
60
LAMPIRAN
Lampiran 1. Lay out Penelitian
a. Lay Out penelitian pada Laboratorium
b. Lay Out penelitian pada Lahan
1. Rancang Acak Kelompok Lengkap
C1P1 C2P1 C3P1 C4P1 C2P2 C2P1
C4P1 C1P1 C3P2 C1P1 C4P2 C2P2
C1P2 C4P2 C2P2 C4P2 C1P2 C3P1
C3P2 C3P1 C1P2 C3P2 C2P1 C4P1
61
Keterangan
Komposisi bahan pembawa (C1) Gambut + 1 % (w/w) gula + 10% (w/w) arang aktif+ 2% (w/w) CaCO3
(C2) Gambut + Kaolin (2:1 w:w) + 2,5% (w/w) CaCO3
(C3) kulit pisang + 40% (w/w) zeolit(C4) Debu Vulkanik + 15% (v/w) air kelapa + 0,1%(v/w) bahan perekat.
Bahan pengemas(P1) Plastik(P2) Alumunium foil
2. Lay out Jarak Tanam
IRIGASI
C1P1
DRAINASE
RIGASI
C2P1
DRAINASE
RIGASI
C3P1
DRAINASE
C4P1 C2P2 C2P1
C4P1 C1P1 C3P2
C1P1 C4P2 C2P2
C1P2 C4P2 C2P2
C4P2 C1P2 C3P1
C3P2 C3P1 C1P2
C3P2 C2P1 C4P1Blok 1 Blok 2 Blok 3
100 cm
120 cm
SALURAN IRIGASI UTAMASALURAN IRIGASI UTAMA
62
Keterangan
Tanaman Sampel (S) : 3Tanaman Korban (K) : 3Jumlah Tanaman : 30/Petak
Lampiran 2. Komposisi Media
1. Media Luria Bertani Cair/La. Tryptone = 10 mlb. Yeast Extract = 5 gramc. NaCl = 10 gramd. Aquadest = 1000 mle. pH = 7,2
2. Media Luria Bertabi Aagar/La. Tryptone = 10 mlb. Yeast Extract = 5 gram
X X X X X
X K1 X S3 X
X X S2 X X
X K2 X K3 X
X X S1 X X
X X X X X
20 20
63
c. NaCl = 10 gramd. Agar = 15 %e. Aquadest = 1000 mlf. pH = 7,2
3. Media Ekstrak Tanah Agar (Allen, 1957 cit johnson etal., 1960)a. Glukosa : 1 gb. K2HPO4 : 0,5 gc. Agar : 15 gd. Aquades Steril : 900 mle. Ekstrak tanah : 250 ml
Cara membuat :- Ekstrak tanah
Ekstrak tanah dibuat dengan mengautoklav 1.000gram contoh tanah yang ditambahkan 1 lier aquadessteril selama 30 menit. Kemudian ditambahkansedikit kalsium karbonat dan suspensi tanahdisaring dengan kertas saring ganda hinggadiperoleh cairan jernih.
64
Lampiran 3. Skema Perbanyakan isolat Rhizobacteri
indigenous Merapi
Gambar 2. Skema alur perbanyakan isolat MA, MB dan MD
Gambar 3. Skema alur pembuatan inokulum campuran
Sumber Isolat
LBA
1 ose
Inkubasi pada suhu ruang selama 48 jam
Inokulasi
Biakan murni
LBC
1 ose
Suhu ruang selama 48 jam
Inokulasi
Rotary shaker
Inkubasi
Gambar 1. Skema alur pembuatan biakan murni isolat bakteri MA, MBdan MD
C1 C2 C3 C4MA MB MD
10 ml Isolat
100 ml LBC per erlenmeyer
10% per isolat (1 ml) setiap
erlenmeyer
Diinokulasikan dan dicampur
Inkubasi selama 48 jam di rotary shaker
Suhu ruangan
65
Gambar 4. Formulasi inokulum padat
P1
Plastik
P2
Alumunium foil
(C1P1, C2P1, C3P1, C4P1, C1P2, C2P2, C3P2, C4P2)
50 gr Carrier
C1 C2 C3 C4
15 ml Inokulum campuran
66
Lampiran 4. Kebutuhan inokulum campuran Rhizobacteri
Indigenous Merapi
Kebutuhan inokulum campuran per perlakuan 10 ml.
Jumlah perlakuan yang membutuhkan inokulum sebanyak 8
perlakuan dan setiap perlakuan memiliki 3 ulangan
sehingga kebutuhan inokulum campuran yaitu 8x3x10ml=
240 ml.
Total kebutuhan inokulum campuran = 240 ml
Total inokulum MA = 80 ml
Total inokulum MB = 80 ml
Total inokulum MD = 80 ml
67
Lampiran 5. Kebutuhan benih padi IR 64
Jumlah tanaman per petak 30 tanaman dikalikan 2tanaman per lubang tanam, sehingga kebutuhan tanamanper pertak 60 tanaman.
Jumlah petak = 24
Kebutuhan total tanaman 1.440 tanaman diasumsikanmenjadi 1.500 butir benih.
Bobot 1000 butir benih padi IR 64 = 27 gram
Kebutuhan benih padi IR 64 = 1.500 x 27 1000 = 40,5 gram benih
68
Lampiran 6. Kadar Lengas Tanah
Penyiraman 6 hari sekali1 11,50 %2 12,70 %3 12 %
rata-rata 12 % Sumber : Agung_Astuti dkk (2013)
70
Lampiran 7. Kebutuhan Pupuk
A. Kebutuhan pupuk per hektar :
Pupuk kandang = 25.000 kg/ha
Urea = 200 kg/ha
SP-36 = 150 kg/ha
KCl = 100 kg/ha.
B. Kebutuhan pupuk per petak
C. Kebutuhan pupuk susulan
No Pupuk Pupukdasar
Pupuksusulan1 (14HST)
Pupuksusulan2 (30HST)
Pupuksusulan3 (40HST)
TotalKebutuhanpupuk
Totalkebutuh
anpupuk(3
blok)
1. Kandang 3 kg - - - 3 kg 9
kg
2. Urea - 24 g 24 g 24 g 72 g 216 g
3. SP-36 18 g - - - 18 g 54 g
4. KCl - 12 g - 12 g 24 g 72 g