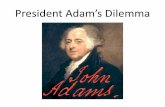Game Theory, Prisoners Dilemma, Hukum Persaingan Usaha, Menghancurkan Kartel
Transcript of Game Theory, Prisoners Dilemma, Hukum Persaingan Usaha, Menghancurkan Kartel
ii
DAFTAR ISI
HALAMANJUDUL.............................................................................................. iBAB I.................................................1PENDAHULUAN...........................................11.1Latar Belakang........................................1
1.2Pokok Permasalahan....................................71.3Tujuan Penulisan......................................7
1.4Kajian Pustaka........................................81.4.2 Dasar pemidanaan suatu perbuatan.................9
1.4.3 Makna perbuatan jahat (crime): Apa itu kejahatan.111.5Metode Penelitian....................................17
1.6Sistematika Penulisan................................19
BAB II...............................................22DASAR PENGKRIMINALISASIAN SUATU PERBUATAN............222.1Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dan Kebijakan Hukum
Pidana (Penal Policy)...................................222.1.1 Arti kebijakan criminal (criminal policy) dan
kebijakan hukum pidana (penal policy) dan hubunganantara keduanya..................................22
2.1.2 Manfaat perumusan kebijakan pidana..............252.2Kriteria penentuan suatu perbuatan sebagai tindak
pidana/kejahatan (crime)..............................272.3Tujuan Hukum Pidana..................................30
Gulden regel............................................30Menghindari main hakim sendiri.............................31
2.4Fungsi sanksi pidana.................................322.3.1 Retribusi.......................................33
Universitas Indonesia
iii
2.3.2 Deteren atau efek jera..........................34
2.3.3 Pelumpuhan (incapacitation)........................352.3.4 Rehabilitasi....................................35
2.3.5 Restoratif......................................35
BAB III..............................................38PENGERTIAN KARTEL DAN DASAR KRIMINALISASI KARTEL.....383.1Pengertian kartel secara umum........................38
3.2Pengertian kartel berdasarkan unsur Pasal 11 UUNo.5/1999............................................39
3.3Ciri-ciri kartel.....................................423.4..........................................Bentuk kartel
.....................................................431. The minor cartelist...................................43
2. The incompetent cartelist..............................443. The unlucky cartelist..................................45
4. The naïve cartelist....................................453.5.............................Dasar Kriminalisasi Kartel
.....................................................463.4.1 Terkait makna (arti) kejahatan: kartel merupakan
suatu kejahatan..................................463.4.1.1.......Berdasarkan pendekatan teori normatif
...........................................463.4.1.2 Berdasarkan pendekatan konsekuensi perbuatan
...........................................493.4.1.3.........Berdasarkan kriteria-kriteria untuk
menentukan suatu perbuatan suatu kejahatan.493.4.2 Terkait tujuan hukum pidana.....................51
3.4.3 Terkait fungsi hukum pidana.....................523.4.4 Dampak buruk kartel.............................53
3.4.4.1........Kartel secara analogis dan asosiatifmerupakan pencurian........................53
Universitas Indonesia
iv
3.4.4.2. Pengalihan surplus konsumen kepada produsenmerupakan pencurian sehingga perbuatanpengalihan tersebut dikriminalisasi........55
3.4.4.3 Kartel menyebabkan kerugian ekonomi terhadapkonsumen, pelaku usaha, dan kesejahteraanumum.......................................58
BAB IV...............................................70STRATEGI PRISONER’S DILEMMA: DILEMA PENDEKATAN SANKSIPIDANA PENJARA, SANKSI PIDANA DENDA, DAN/ATAU GANTIRUGI PERDATA.........................................704.1Prisoner’s Dilemma......................................71
4.1.1 Sejarah penentuan sanksi atas kartel di AmerikaSerikat..........................................71
4.1.2 Strategi Prisoner’s Dilemma dan tarik-menarik antarasanksi pidana penjara, pidana denda dan/atau gantirugi perdata dalam skema strategi prisoner’s dilemma. 81
4.2. Cara Merumuskan Kebijakan Sanksi Terhadap Kartel UntukMeningkatkan Efek Jera di Amerika Serikat............894.2.1 Gambaran umum tentang Teori Efek Jera Kartel (Cartel
Deterrence)........................................894.2.2 Teori Efek Jera Kartel Awal di Amerika Serikat
(Sebelum Program Corporate Leniency 1993)............904.2.3 Dampak Corporate Leniency Program 1993 Amerika Serikat
dalam mengurangi kartel (Efek Jera Kartel).......924.2.3.1 Kunci observasi pertama: dua ciri utama dari
Corporate Leniency Program 1993.................944.2.3.2 Kunci observasi kedua: Interdependensi p dan
F..........................................964.3......Kemungkinan penerapan strategi prisoner’s dilemma di
Indonesia untuk menghancurkan kartel dan meningkatkanefek jera sanksi atas kartel.........................97
4.4.Kerancuan dan/atau Absurditas Penentuan Sanksi TerhadapKartel Berdasarkan UU No. 5/1999....................100
Universitas Indonesia
v
4.4.1 Pasal 47 dan 48 tidak merumuskan secara jelassubyek sanksi...................................101
4.4.2 Sanksi pidana penjara untuk orang-perseorangandihilangkan.....................................102
4.4.3 Absurditas penentuan “denda” administrasi dan“denda” pidana..................................103
4.4.4 Metode penghitungan lama kurungan akibat tidakdibayarnya pidana denda dalam Pasal 48 UU No.5/1999 tidak sesuai dengan metode penghitungan yangditentukan pasal 30 ayat (4) KUHP...............105
4.5.. Kaitan Antara Penentuan Sanksi Pidana Penjara, PidanaDenda, dan/atau Ganti Rugi Perdata Dalam StrategiPrisoner’s Dilemma Dengan Prinsip Ultimum Remedium.....107
BAB V...............................................110PENUTUP.............................................1105.1Simpulan............................................1105.2Saran...............................................111
DAFTAR PUSTAKA......................................113
Universitas Indonesia
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pasal 11 juncto 48 ayat (1) Undang-Undang No. 5
tahun 1999 tentang Larangan Praktek Anti Monopoli dan
Persaingan Usaha Sehat (UU No.5/1999) menentukan bahwa
kartel dikriminalisasi. Namun, tidak ada penjelasan
tentang dasar kriminalisasi kartel baik dalam batang
tubuh UU No.5/1999 maupun dalam penjelasannya. Selain
itu, naskah akademik undang-undang tersebut tidak
membahas tentang dasar kriminalisasi kartel maupun cara
menentukan sanksi pidana atas kartel. Padahal dalam
penerapan UU No.5/1999, Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) secara implisit sudah menjatuhkan sanksi
pidana dalam kasus kartel minyak goreng,1 atau
setidaknya KPPU tidak secara eksplisit menyatakan
sanksi apa yang dijatuhkan atas para terlapor dalam
kasus kartel minyak goreng serta pasal yang digunakan
sebagai dasar penjatuhan hukuman.2
Dalam putusan KPPU tentang kartel minyak goreng,
KPPU “menghukum Terlapor ... untuk membayar denda
sebesar ... yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai1 Pembacaan Putusan Perkara Industri Minyak Goreng Sawit di
Indonesia. Bisa dilihat di http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=1140&encodurl=06%2F07%2F10%2C12%3A06%3A32. Kunjunganterakhir tanggal 7 Juni 2010.
2 Ibid.
Universitas Indonesia
2
Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran ...(Pendapatan
Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).”3 “Denda
pelanggaran” kelihatannya merupakan istilah yang
merujuk pada sanksi pidana. Hal ini sesuai dengan
rumusan Pasal 48 ayat (1) UU No.5/1999 yang menentukan
“Pelanggaran terhadap ketentuan .... diancam pidana
denda.” Meskipun dalam praktiknya, KPPU tidak pernah
secara eksplisit menjatuhkan sanksi pidana denda.
Bahkan, bisa dikatakan pasal 48 UU No.5/1999 merupakan
pasal mati.
Kesimpangsiuran seperti yang dijelaskan di atas
berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (criminal policy).
Kebijakan kriminal dibagi menjadi kebijakan pidana
penal (sanksi pidana) dan non-penal. Di sinilah prinsip
ultimum remedium tercermin, yaitu bahwa tidak semua
perbuatan yang merugikan (dalam hukum positif) perlu
dihukum dengan penjatuhan sanksi pidana. Kebijakan
pidana, baik penal maupun non-penal pada akhirnya
bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang
terkait erat dengan kebijakan kesejahteraan sosial
(social welfare policy). Hal ini dikumandangkan dalam laporan
Kursus Latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI
di Tokyo tahun 1979 sebagai berikut:
“Most group members agreed some discussion that “protection of
the society” could be accepted as the final goal of criminal policy,
although not the ultimate aim of society, which might perhaps be
3 Ibid.
Universitas Indonesia
3
described by terms like “happiness of citizens”, “a wholesome and
cultural living”, “social welfare” or equality”.4
Terkait kebijakan pidana kartel, perlindungan
masyarakat, yang mencakup perlindungan atas
kesejahteraan ekonomi, menjadi tujuan utama atau tujuan
akhir dari kebijakan sosial (yang terdiri dari
kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan
perlindungan sosial). Oleh karena itu, hal lain yang
perlu diperhatikan adalah dinamika interaksi antara
sanksi dalam ranah kebijakan pidana dan sanksi di luar
ranah kebijakan pidana (seperti sanksi perdata dan
administrasi) dalam menciptakan perlindungan masyarakat
atas kesejahteraan ekonomi. Kajian terhadap
fleksibilitas penjatuhan sanksi pidana dan sanksi
lainnya seperti sanksi perdata dan administrasi bisa
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sanksi
tersebut sehingga pada gilirannya dapa meningkatkan dan
memaksimalkan fungsi efek jera dari sanksi. Berhubung
kebijakan pidana juga terkait erat dengan kesejahteraan
sosial, maka kajian tentang fleksibilitas sanski (penal
maupun non-penal) merupakan salah satu cara untuk
mencapai tujuan perlindungan masyarakat (kesejahteraan
ekonomi). Dengan kata lain, penjatuhan sanksi harus
memiliki fungsi kemanfaatan (utilitarianisme) yang
4 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakanke-II, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002), hal 2.
Universitas Indonesia
4
indikatornya bisa dilihat dari meningkatnya atau
maksimalnya efek jera dari sanksi yang dijatuhkan.
Kartel pada dasarnya merupakan ancaman bagi
kesejahteraan ekonomi sehingga perumusan kebijakan
pidana merupakan suatu syarat untuk menjamin
kesejahteraan ekonomi tersebut. The Organisation for Economic
Co-operation and Development (“OECD”) melaporkan bahwa 16
(enam belas) kartel global yang terdeteksi menyebabkan
hilangnya efisiensi ekonomi dalam perdagangan lebih
dari US$ 55 milyar.5 Dengan kata lain, hak ekonomi
konsumen global sebesar US$ 55 milyar dicuri atau
ditipu oleh pelaku kartel. OECD juga menyatakan bahwa
kartel merupakan bentuk pelanggaran paling buruk dari
hukum persaingan usaha.6 Kementerian Perkembangan
Ekonomi (Ministry of Economic Development) Selandia Baru
dalam laporan Regulatory Impact Assessment tentang dasar
kriminalisasi kartel di Selandia Baru pada awal tahun
2010 menjelaskan bahwa kartel merupakan kejahatan yang
menyebabkan hilangnya efisiensi ekonomi.7 Harga5 OECD 2006, Hard Core Cartels – Third Report on the Implementation of the
1998 OECD Recommendation, dalam OECD Journal of Competition Law and Policy,Vol 8 no 1.
6 R. Hewitt Pate, Anti-cartel Enforcement: The Core Antitrust Mission,disampaikan kepada the British Institute of International and Comparative Lawpada Third Annual Conference on International and Comparative Competition Law(May 16, 2003), Lihat:http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/201199.htm (kunjunganterakhir tanggal 20 Mei 2010).
7 Manatu Ohanga, Cartel Criminalisation, Ministry of EconomicDevelopment, Discussion Document for Regulatory Impact Assessment,(Ministry of Economic Development: New Zealand, January 2010), hal18.
Universitas Indonesia
5
pasar/kompetitif barang dan/atau jasa tidak tercipta
karena pelaku usaha terkait meniadakan kompetisi
diantara mereka. Umumnya harga yang tercipta dari
kartel jauh lebih tinggi dari harga pasar/kompetitif
karena pelaku usaha terkait ingin meraup marjin
keuntungan yang lebih besar dari penjualan per satuan
produk dan/jasa mereka. Dampak buruk ini tidak hanya
merugikan konsumen, namun juga pelaku usaha lain
(baru), persaingan, kualitas barang, dan terhadap
semangat inovasi dan pengembangan teknologi.
Selanjutnya, terdapat masalah terkait dengan
penentuan sanksi atas kartel. Sanksi atas kartel pada
dasarnya terdiri dari, berdasarkan urutan hierarki,
sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana.
Urutan hierarki ini tidak secara eksplisit ditentukan
dalam UU No.5/1999, namun merupakan pendapat sarjana
dalam menginterpretasi ketentuan sanksi.8 Sementara
itu, parameter atau takaran penentuan sanksi tersebut
masih terkesan tidak jelas. Pasal 47 ayat (2) f
menentukan bahwa KPPU mempunyai kewenangan untuk
menetapkan pembayaran ganti rugi, sementara pasal 47
ayat (2) g memberikan kewenangan kepada KPPU untuk
menetapkan denda administrasi.
8 Knud Hansen, Peter W. Heermann, et.al., Komentar HukumUndang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha TidakSehat, edisi kedua (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für TechnischeZusammenarbeit (GTZ) GmbH dan Penerbit Katalis, 2002), hal 22.
Universitas Indonesia
6
Masalah yang timbul adalah ketidakjelasan dasar
ganti rugi dan ketidakjelasan perbedaan denda
administrasi dengan denda pidana. Ganti rugi merupakan
konsep yang dikenal dalam ranah hukum perdata yang batu
ujinya terletak pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPer). Pasal 1365 KUHPer menyatakan
bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk
mengganti kerugian tersebut.” Pertanyaannya adalah
apakah KPPU merupakan pihak yang dirugikan? Padahal,
kartel merupakan tindakan yang menyebabkan kerugian,
terutama, terhadap konsumen. Terkait denda
administrasi, walaupun Pedoman KPPU tentang ketentuan
Pasal 47 tentang tindakan administratif menentukan
penghitungan denda administrasi, KPPU dalam praktiknya
tidak menjelaskan dasar perhitungan jumlah denda
administrasi yang dijatuhkan kepada para terlapor.9
Masalah yang muncul dari ketidakjelasan parameter
penentuan sanksi ini mempunyai akibat yang buruk
terkait konteks kepastian dan keadilan hukum. Para
terlapor atas pelanggaran ketentuan kartel berdasarkan
UU No.5/1999 dijatuhkan hukuman denda dengan jumlah
tertentu tanpa mengetahui dasar penentuan sanksi
tersebut.
9 Lihat Pembacaan Putusan Perkara Industri Minyak GorengSawit di Indonesia, op.cit.
Universitas Indonesia
7
Kajian tentang penentuan sanksi atas kartel menjadi
penting untuk mengukur tingkat efisiensi dan
efektifitas sanksi untuk menciptakan efek jera terhadap
pelaku kartel. Kebijakan perumusan sanksi yang tidak
jelas juga mempunyai dampak terhadap prinsip ultimum
remedium. Pada dasarnya, prinsip ultimum remedium
menyatakan bahwa penyelesaian pidana harus menjadi
alternatif penyelesaian terakhir setelah semua semua
alternatif penyelesaian masalah telah dilakukan dan
gagal atau tidak efektif. Ketidakjelasan penentuan
sanksi atas kartel berdampak kepada efektifitas dan
efisiensi sanksi sehingga tidak jelas kapan sanksi
pidana harus dijatuhkan. Padahal sanksi pidana
dijatuhkan setelah sanksi lainnya tidak efektif
dan/atau efisien.
Ketiadaan naskah akademik yang komprehensif dan
kajian tentang (i) dasar kriminalisasi kartel dan (ii)
penentuan sanksi atas kartel merupakan salah satu
akibat dari transplantasi nilai-nilai hukum asing ke
dalam hukum Indonesia. Pasca krisis moneter pada tahun
1998, Indonesia terlilit hutang yang besar akibat
hutang luar negeri. Pada tahun 1996 hutang luar negeri
Indonesia adalah USD 128,941 milyar,10 pada tahun 1997
10 Emmy Hafild, Daris Furqon, et.al., Addicted to Loan: The World BankFoot Prints in Indonesia, WALHI (Indonesian Forum for Environment), hal1. Lihat http://www.asienhaus.de/public/archiv/WB-and_Indonesia_Walhi_paper.pdf. Kunjungan terakhir 22 Juni 2010.
Universitas Indonesia
8
sebesar USD 136,173 milyar,11 dan terjadi lonjakan
besar pada tahun 1998 yaitu sebesar USD 150,875
milyar.12 International Monetary Fund, yang merupakan pemberi
pinjaman terbesar,13 mendesak agar Indonesia membuat
legislasi tentang hukum persaingan usaha untuk
melindungi kepentingan investor yang berkepentingan di
Indonesia. Pada tahun 1999 disahkan UU No.5/1999 yang
rumusan pasalnya sepintas lalu merupakan transplantasi
dari hukum persaingan usaha di Amerika Serikat.
Contohnya, pengenalan istilah trust dalam UU No.5/1999
padahal hukum Indonesia tidak mengenal lembaga trust.
Pada tahun 2008, legislator Australia mengesahkan
ketentuan yang mengkriminalisasi kartel.14 Sementara
Selandia Baru, pada awal tahun 2010, Selandia Baru
membahas tentang kemungkinan pengkriminalisasian
kartel.15 Dasar kriminalisasi kartel dikaji secara
mendalam melalui Regulatory Impact Assessment tentang
kriminalisasi kartel. Dalam RIA tersebut, terlihat
jelas bahwa kebijakan pidana bertujuan untuk
meningkatkan efek jera dari sanksi atas kartel. Alasan
kriminalisasi kartel juga tercermin dari paparan kajian
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Trade Practices Amendment (Cartel Conduct and other Measures) Bill 2008.Lihat http://www.mondaq.com/australia/article.asp?articleid=93050.Kunjungan terakhir tanggal 22 Juni 2010.
15 .Manatu Ohanga,op.cit., hal. 18.
Universitas Indonesia
9
tersebut tentang sifat kartel yang sulit dideteksi,
terorganisasi dengan baik, dilakukan oleh mereka yang
punya kedudukan terpandang dalam masyarakat, merugikan
konsumen, dan yang lebih sulit lagi adalah untuk
diatasi.
Selain alasan di atas, RIA Selandia Baru merupakan
rujukan yang berguna karena RIA tersebut juga
menggunakan kajian dari OECD tentang kartel. Kajian
OECD merupakan rujukan yang cukup universal karena di
dalamnya terkandung studi internasional tentang
kriminalisasi kartel dan rangkuman tentang kebijakan
kartel dari semua negara anggota OECD, termasuk negara-
negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Korea
Selatan, Kanada, Brazil, Australia, Meksiko, dan
Britania Raya.16 Kebijakan-kebijakan dari semua negara
anggota OECD tersebut bisa menjadi cerminan dari
kebijakan kriminalisasi kartel maupun penentuan sanksi
atas kartel yang universal.
Terkait dasar penentuan sanksi dan efektifitas
serta efisiensi sanksi, Amerika Serikat merupakan
rujukan studi yang cukup berguna. Hukum tentang
persaingan usaha di Amerika Serikat diletakkan pada
Sherman Act 1890 dan Clayton Act 1914. Kedua undang-undang
ini merupakan batu pondasi dari hukum persaingan usaha
16 OECD, Hard Core Cartels: Third Report on the implementation of the 1998Council Recommendation. Lihat dihttp://www.oecd.org/dataoecd/58/1/35863307.pdf (kunjungan terakhir25 Juni 2010).
Universitas Indonesia
10
di Amerika Serikat serta merupakan salah ketentuan
hukum persaingan paling tua di dunia. Dalam menentukan
sanksi, mengukur efektifitas dan efisiensi sanksi atas
kartel, serta meningkatkan efek jera dari sanksi atas
kartel, Department of Justice Amerika Serikat menggunakan
game theory prisoner’s dilemma. Prisoner’s dilemma terjadi
ketika polisi memisahkan 2 pihak ke ruang yang berbeda
dan masing-masing diberikan tawaran yang sama. Strategi
ini efektif ketika 2 (dua) pihak berkehendak untuk
mengejar kepentingan masing-masing dan bertindak secara
rasional-egois (rationally selfish manner).17 Metamorfosis
penentuan sanksi atas kartel di Amerika Serikat dari
pra-1993, tahun 1993-2004, serta pasca 2004 menunjukkan
bagaimana prisoner’s dilemma merupakan strategi yang tepat
dalam menentukan sanksi atas kartel yang efektif dan
efisien. Strategi prisoner’s dilemma menunjukkan tarik-
menarik antara sanksi pidana penjara, pidana denda, dan
ganti rugi perdata sehingga dapat diukur dengan lebih
akurat kapan sanksi tertentu dijatuhkan dengan tujuan
untuk menciptakan efek jera yang maksimal.
Alasan lain mengapa Penulis merujuk pada kebijakan
Amerika Serikat terkait penentuan sanksi atas kartel
dan strategi untuk menangani kartel adalah karena (i)
hukum persaingan usaha Amerika Serikat merupakan yang
paling tua umurnya, (ii) hukum persaingan usaha Amerika17 Christopher R. Leslie (1), Symposium The Antitrust
Enterprise: Principle and Execution, Antitrust Amnesty, Game Theory, andCartel Stability, Journal of Corporation Law, 31 J. Corp. L. 453, 2006.
Universitas Indonesia
11
Serikat banyak dirujuk dalam perumusan kebijakan kartel
dan bahkan Amerika Serikat merupakan salah satu negara
pertama yang mengkriminalisasi kartel, dan (iii) di
satu sisi, strategi ekonomi (game theory), berkembang
pesat di Amerika Serikat dan, di sisi lain, perkawinan
disiplin ilmu hukum dan ekonomi melahirkan strategi
yang efektif dan efisien dalam penanganan kejahatan
kartel.
1.2 Pokok Permasalahan
1. Bagaimana dasar kriminalisasi kartel di Indonesia?
2. Bagaimana dasar kriminalisasi kartel di Selandia
Baru dan di Amerika Serikat?
3. Bagaimana kemungkinan strategi prisoner’s dilemma
diterapkan untuk meningkatkan efek jera dari
sanksi kartel di Indonesia?
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk memaparkan dasar kriminalisasi kartel
berdasarkan pasal 11 juncto pasal 48 UU No. 5 tahun
1999, serta perumusan sanksi atas kartel
berdasarkan Pasal 47 dan 48 UU No. Tahun 1999.
2. Untuk memaparkan dasar kriminalisasi kartel di
Selandia Baru dan Amerika Serikat dan selanjutnya
digunakan sebagai model untuk membandingkan dasar
Universitas Indonesia
12
kriminalisasi kartel antara Indonesia dengan
Selandia Baru dan Amerika Serikat serta penentuan
sanksi atas kartel.
3. Untuk memaparkan tentang kemungkinan penerapan
strategi prisoner’s dilemma untuk meningkatkan efek
jera dari sanksi kartel di Indonesia.
1.4 Kajian Pustaka
Perkembangan hukum yang dinamis menyebabkan
diperlukannya pengaturan pidana dalam Undang-undang
selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Alasannya adalah karena kebutuhan hukum dalam hal
ketentuan substansi hukum pidana maupun sanksinya yang
tidak lagi terakomodasi oleh KUHP. Dalam realitanya,
banyak Undang-Undang di luar KUHP, misalnya Undang-
Undang tentang Lingkungan Hidup, Hak Kekayaan
Intelektual, Persaingan Usaha dan Perbankan yang memuat
ketentuan pidana. Selain itu, banyak pandangan yang
menyatakan bahwa legislator di Indonesia bahkan tidak
memahami asas-asas tertentu dalam KUHP apalagi
menyelaraskan asas yang ada dalam KUHP dengan Undang-
Undang yang disusun.
Akibat perkembangan hukum dan realitas sosial yang
tidak memungkinkan diterapkannya asas-asas dalam buku
kesatu KUHP yang secara konsisten. Meskipun Pasal 103
KUHP memungkinkan penyimpangan asas, namun pertanyaan
Universitas Indonesia
13
utama adalah asas-asas mana saja yang bisa disimpangi
dan tidak bisa disimpangi. Misalnya, apakah mungkin
asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP disimpangi? Bila bisa
disimpangi, apakah ada persyaratan khusus untuk rezim
pidana tertentu seperti terorisme? Masalah selanjutnya
adalah terkait dengan perumusan ketentuan pidana dalam
Undang-Undang lain yang tidak secara eksplisit dan
struktural mengatur penyimpangan dari buku kesatu KUHP
sehingga terjadi kerancuan apakah asas-asas tertentu
dalam KUHP telah disimpangi. Kerancuan ini mempunyai
dampak yang besar terhadap pemahaman ketentuan pidana
dalam Undang-Undang di luar KUHP. Misalnya, dalam
konteks Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual
dan Hukum Persaingan Usaha, pendekatan penyelesaian
yang dianut adalah, secara hierarki, penyelesaian
administratif, perdata, dan terakhir pidana. Urutan
hierarki ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU
tersebut. Artinya, hanya jika penyelesaian
administratif gagal maka penyelesaian perdata akan
ditempuh, kemudian hanya jika penyelesaian perdata
gagal maka penyelesaian pidana akan ditempuh.
Pendekatan ini menggunakan asas ultimum remedium yang
merupakan salah satu asas penting dalam KUHP.
Pada dasarnya, prinsip ultimum remedium menyatakan
bahwa penyelesaian pidana harus menjadi alternatif
penyelesaian terakhir setelah semua semua alternatif
penyelesaian masalah telah dilakukan dan gagal atau
Universitas Indonesia
14
tidak efektif. Pembahasan prinsip ini terkait erat
dengan tujuan dan fungsi pemidanaan.
1.4.2Dasar pemidanaan suatu perbuatan
Dasar kriminalisasi yang berbeda mengakibatkan
perbedaan pemaknaan dan pendekatan terhadap asas
ultimum remedium dalam hal dasar filosofi, batas, dan
aplikasi praktisnya. Senada dengan tujuan yang berbeda
ini, Muladi menyatakan karena tujuannya bersifat
integratif maka perangkat tujuan pemidanaannya adalah :
(a) pencegahan umum dan khusus, (b) perlindungan
masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, dan
(d) pengimbalan/pengimbangan. Untuk mengilustrasikan
keterkaitan erat tujuan pemidanaan dengan prinsip
ultimum remedium, Eva Achjani Zulfa menyatakan “Jika
posisi pemidanaan sebagai ultimum remedium, maka
penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan
pendekatan restoratif justru menjadi primum
remedium.”18
Menurut Mardjono Reksodiputro tujuan
pemidanaan itu harus memperhatikan hak asasi manusia.
Menurutnya, konsep ke-1 RUU KUHPidana yang diajukan
pada tahun 1993 juga memperhatikan perlindungan
18 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentangKemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek PenegakanHukum Pidana), Ringkasan Disertasi, (Jakarta: UniversitasIndonesia, 2009), hal 30.
Universitas Indonesia
15
terhadap hak asasi warga masyarakat, dengan didukung
oleh tiga prinsip yaitu sebagai berikut: 19
a. hukum pidana (juga) dipergunakan untuk menegaskan
atau menegakkan kembali nilai – nilai sosial dasar
(fundamental social values) perilaku hidup
bermasyarakat (dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang dijiwai oleh falsafah dan ideologi
negara Pancasila);
b. hukum pidana (sedapat mungkin) hanya dipergunakan
dalam keadaan di mana cara lain melakukan
pengendalian sosial (social control) tidak (belum)
dapat diharapkan keefektifannya; dan
c. hukum pidana (yang telah mempergunakan kedua
pembatasan (a dan b diatas) harus diterapkan
dengan cara seminimal mungkin mengganggu hak dan
kebebasan individu, tanpa mengurangi perlunya juga
perlindungan terhadap kepentingan kolektifitas
dalam masyarakat demokratik yang moderen.
Akibatnya adalah ketidakjelasan kapan penyelesaian
pidana seharusnya ditempuh. Selain itu, banyak asas
lain yang terkait asas ultimum remedium yang juga
menjadi tidak jelas makna dan penerapannya. Misalnya,
dalam hal perbuatan menghancurkan atau merusakkan
barang Bab XXVII pasal 406 ayat 1 KUHP. Pasal 406 ayat
1 berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan19 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Mengkritisi RUU KUHPidana dalam
perspektif HAM, Konsultasi Publik “Perlindungan HAM Melalui ReformasiKUHP” Hotel Santika Slipi Jakarta, 3 - 4 Juli 2007, kerjasamaKOMNAS HAM dan Aliansi Nasional Reformasi Indonesia.
Universitas Indonesia
16
hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat
dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam
dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima
ratus rupiah.” Bila seseorang menghancurkan kaca
jendela tetangganya dengan sengaja, maka orang tersebut
dapat dijatuhi sanksi pidana penjara dan sekaligus
digugat secara perdata dan dijatuhkan sanksi ganti rugi
berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata. Pertanyaan yang
muncul adalah apakah masalah belum selesai dengan
adanya penjatuhan sanksi ganti rugi secara perdata?
Apakah penjatuhan sanksi pidana menyelesaikan masalah
atau malah mempersulit masalah yang sudah ada? Contoh,
kasus Nenek Minah yang dijatuhkan sanksi pidana penjara
1 bulan 15 hari dengan hukuman percobaan 3 bulan karena
mencuri 3 buah kakao. Banyak kalangan masyarakat yang
menilai bahwa hukum di Indonesia tidak mengakomodasi
asas keadilan dan hanya secara buta menegakkan
kepastian hukum. Permasalahan seperti ini berakar pada
ketidakjelasan dasar kriminalisasi di Indonesia.
Seperti yang diungkapkan di paragraf sebelumnya
bahwa ketidakjelasan dasar kriminalisasi mempunyai
dampak kepada asas-asas lain, yaitu prinsip
penyelesaian perdata tidak meniadakan pidana yang
dianut dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana
Korupsi, lex specialis derogat legi generalis dalam kaitan
Universitas Indonesia
17
penyimpangan asas buku kesatu KUHP oleh Undang-Undang
di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana, dan teori
pemidanaan yaitu tentang syarat sebuah perbuatan
diklasifikasikan tindakan pidana. Dalam konteks
penentuan kriteria tindak pidana, kriteria untuk
menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana
tergantung pada tujuan apakah pada umumnya yang akan
dicapai pembentuk undang-undang dengan menentukan suatu
perbuatan sebagai perbuatan pidana.20 Prinsip ultimum
remedium menjadi relevan dalam pembahasan penentuan
kriteria tindak pidana karena jika sebuah tindakan bisa
diselesaikan dengan penyelesaian di luar penyelesaian
pidana maka tindakan tersebut masih bisa diperdebatkan
apakah masuk dalam kriteria tindak pidana atau tidak.
Misalnya, membunuh, memperkosa, dan mencuri merupakan
tindakan yang dikriminalisasi di hampir semua sistem
pemidanaan di dunia. Artinya, untuk ketiga kategori
perbuatan tadi bisa dikatakan mutlak atau jelas masuk
ke dalam kategori tindakan pidana. Akibatnya adalah
tidak mungkin diselesaikan secara perdata maupun
administrasi. Sedangkan, untuk perbuatan yang berada di
antara ranah perbuatan perdata dan/atau pidana, maka
sulit untuk menentukan secara jelas apakah penyelesaian
pidana itu sebagai primum remedium atau ultimum
remedium atau di antara keduanya. Jika digambarkan
20 Roeslan Saleh, Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, SinarGrafika (1988), hal 73.
Universitas Indonesia
18
berdasarkan bagan/spektrum hitam-putih, maka perbuatan
mencuri, membunuh, dan memperkosa masuk dalam kategori
warna hitam, sementara tindakan yang terkait dengan
rezim persaingan usaha maupun hak kekayaan intelektual
masuk dalam area yang lebih abu-abu. Banyak kalangan
menilai bahwa pengaturan tentang hak kekayaan
intelektual, contohnya, harusnya hanya masuk ke dalam
ranah hukum perdata dan tidak seharusnya diatur dengan
ketentuan pidana. Kartel merupakan salah satu perbuatan
yang masuk dalam area abu-abu tersebut. Akibat dari
perbuatan yang masuk ke area abu-abu adalah tidak
jelasnya peran hukum pidana di dalamnya. Hal ini
terjadi karena ketidakjelasan penentuan kriteria tindak
pidana.
1.4.3Makna perbuatan jahat (crime): Apa itu
kejahatan
Jean-Paul Brodeur dan Geneviève Ouellet mempertanyakan
apakah, di satu sisi, pertanyaan “apa itu kejahatan?”
bisa diterjemahkan menjadi pertanyaan “apa itu
pembunuhan, penggelapan pajak, atau pemerkosaan?”21 Di
sisi lain, pertanyaan tersebut bisa diartikan secara
umum tanpa rujukan pada perbuatan tertentu seperti
pembunuhan, namun pada sifat (nature) kejahatannya.22
21 Jean-Paul Brodeur dan Geneviève Ouellet, What Is a Crime? ASecular Answer, (Canada: UBC Press, 2004), hal 1.
22 Ibid.
Universitas Indonesia
19
Menurut Jean-Paul Brodeur dan Geneviève Ouellet, ada dua aspek
penting yang masih kabur dari pertanyaan di atas.23
Pertama, apa yang dicari - definisi lengkap atau teori
yang lebih komprehensif? Kedua, apakah kita
mengkriminalisasikan perbuatan/fakta yang sudah ada
atau yang sudah bisa dideskripsikan, atau kita
berkehendak untuk meletakkan dasar normatif untuk
kriminalisasi di masa yang akan datang?
Kedua aspek penting di atas, lebih lengkapnya,
dijelaskan oleh Jean-Paul Brodeur dan Geneviève Ouellet dengan
menggunakan beberapa metode pendekatan sebagaimana
dijelaskan di bawah.
a. Definisi atau teori
Definisi adalah sekumpulan kata-kata yang bisa
disubstitusikan dalam proses pencarian makna sebuah
kata.24 Sebagai substitusi untuk sebuah kata yang
didefinisikan, definisi umumnya hanya sebatas sebuah
kalimat pendek.25 Menurut George W. Keeton dan George
Schwarzenberger beberapa abad sebelum tahun 1955,
kejahatan masih bisa didefinisikan, namun seiring
dengan perkembangan konsep kejahatan yang semakin23 Ibid.
24 Glanville Williams, The Definition of Crime, dalam Current LegalProblems oleh George W. Keeton dan George Schwarzenberger,University College, vol. 8, (London: Stevens and Sons, 1955), hal.108.
25 Jean-Paul Brodeur dan Geneviève Ouellet, op.cit, hal 2.
Universitas Indonesia
20
rumit, maka diperlukan pondasi epistemologi. Dengan
kata lain, kejahatan tidak mungkin didefinisikan pada
saat sekarang karena sumirnya kata-kata yang
mensubstitusikannya. Selain itu, usaha untuk memberikan
keadilan hukum pada saat sekarang ini, umumnya berkutat
berbagai faktor kejahatan yang semakin berkembang.26
a.1 Definisi Faktual
Pendekatan ini lebih menekankan pada perspektif
yang formalistik, yaitu dengan mempostulasikan bahwa
kejahatan adalah pelanggaran hukum positif.27 Tappan
mencontohkan poin tersebut sebagai berikut: “Kejahatan
adalah perbuatan yang dengan sengaja atau lalai
melanggar hukum pidana formil (dalam bentuk statuta
atau case law di sistem common law), yang dilakukan tanpa
dasar pemaaf (justification) atau pembenar (defence) dan
yang bisa dihukum oleh negara.28 Dalam diskursus hukum
klasik, konsep ini dikenal dengan adagium malum
prohibitum.29
a.2 Definisi Normatif
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Paul W. Tappan, Crime, Justice and Correction, (New York: McGraw-Hill Series in Sociology, 1960), hal 10.
29 “Malum prohibitum is an act that is a crime merely because it is prohibited bystatute, although the act itself is not necessarily immoral.” Bryan A. Garner,Blacks Law Dictionary, 8th edition, (Thompson: United States, 1999),hal. 978.
Universitas Indonesia
21
Pendekatan definisi normatif mengambil satu langkah
mundur sebelum membahas reaksi sosial terhadap
perbuatan tertentu dan berusaha mencari alasan-alasan
yang membenarkan kriminalisasi terhadap perbuatan
tertentu.30 Dengan kata, lain terlepas dari apakah
suatu perbuatan dikriminalisasi oleh hukum positif,
pendekatan definisi normatif berusaha menggali alasan
dikriminalisasinya suatu perbuatan, baik berdasarkan
nilai moral, kesusilaan, maupun agama. Dalam diskursus
hukum klasik, konsep ini dikenal dengan adagium malum in
se.31 Sebelum konsep kejahatan berkembang menjadi begitu
rumit, definisi yang berdasarkan konsep rasa sakit
(harm) atau kerusakan (damage) kepada orang lain masih
lazim diterima. Meskipun konsep kejahatan ini merupakan
inti dari ilmu kriminologi, semakin sedikit sarjana
sekarang yang berpendapat bahwa pertanyaan tentang
sifat kejahatan itu bisa diselesaikan dengan merumuskan
definisi kejahatan dalam satu kalimat.32
a.3 Teori Faktual
Teori ini menekankan pada perbuatan-perbuatan yang
dianggap oleh hukum sebagai kejahatan.33 Pendekatan ini30 Jean-Paul Brodeur dan Geneviève Ouellet, op.cit, hal 2.
31 Malum in se is a crime or an act that is inherently immoral, such as murder,arson, or rape. Garner, op.cit.
32 Barone Raffaele Garofalo, Criminology (1885) disadurkanMontclair (New Jersey: Patterson Smith Reprints, 1968), hal 46.
33 Jean-Paul Brodeur dan Geneviève Ouellet, op.cit, hal 2.
Universitas Indonesia
22
adalah ciri utama dari paham formalisme yang menyatakan
bahwa kejahatan adalah produk dari reaksi sosial.34
Durkheim menyatakan bahwa elemen khusus dari kejahatan
adalah keterkaitannya dengan sanksi.35 Perbedaan utama
antara pendekatan teori faktual dengan pendekatan “akal
sehat” atau common sense adalah pendekatan teori faktual
menekankan pada kejahatan dalam dimensi hukum yang utuh
(full legal dimension), sementara pendekatan common sense
menekankan pada sifat dari kejahatan yang serius.
a.4 Teori Normatif
Untuk menentukan kriteria pengkriminalisasian
perbuatan tertentu melalui perbuatan itu sendiri, maka
harus digunakan pendekatan teori normatif.36 Ada dua
variabel dalam pendekatan teori normatif. Variabel
pertama adalah epistimologi. Salah satu Bapak
Kriminologi, Garofalo, berpendapat bahwa disiplin ilmu
kriminologi yang ilmiah bertumpu pada subjek yang
stabil. Untuk memenuhi standar ilmiah ini, Garofalo
mengembangkan teori “kejahatan natural” atau natural
crime, yang hanya berlaku untuk kejahatan berat atau
hard core of criminality. Variabel kedua adalah pragmatisme
yang terdiri dari sistem pemikiran yang merubah34 Ibid.
35 Émile Durkheim, Deux lois de l’évolution pénale L’année sociologique,(1899-1900), hal 65-95 dalam Jean-Paul Brodeur dan GenevièveOuellet, op.cit, hal 2.
36 Jean-Paul Brodeur dan Geneviève Ouellet, op.cit, hal 3.
Universitas Indonesia
23
praktek-praktek yang ada dalam mengkriminalisasikan
berbagai perbuatan.
b. Fakta atau Standar
Langkah selanjutnya adalah mempertanyakan (i) apa
itu kejahatan dengan dasar penelitian terhadap
perbuatan-perbuatan yang pada saat sekarang ini
dianggap oleh hukum sebagai kejahatan atau (ii)
kriteria apa yang harus dipakai untuk menentukan bahwa
perbuatan tertentu merupakan kejahatan di masa yang
akan datang.37 Pendekatan poin (i) dilakukan dengan
menelaah alasan-alasan perbuatan tertentu dianggap
sebagai kejahatan. Sementara itu, pendekatan poin (ii)
terletak pada alam yang lebih ideal, yang bersifat
normatif, dan pada dasarnya subyektif, dimana
argumennya lebih bersifat pembenaran etis daripada
pembuktian empiris.
J.M. van Bemmelen dalam buku “Criminoligie, leerboek der
misdaadkunde”, sejak terbitnya tahun 1942 sampai cetakan
ke-4 pada tahun 1958 berusaha untuk mendapatkan jawaban
atas pertanyaan “apakah kriminalitas/kejahatan?”
Bermelen akhirnya menyimpulkan bahwa “Kejahatan adalah
tiap-tiap kelakuan yang berbahaya dan juga tidak
susila, yang dapat menimbulkan begitu banyak
ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu,
37 Ibid.
Universitas Indonesia
24
sehingga masyarakat itu berhak untuk menyatakan celaan
dan perlawanannya terhadap kelakuan itu dalam bentuk
sengaja membebankan derita yang dikaitkan dengan
kelakuan tersebut.38
Alida Bos menyatakan bahwa “suatu perbuatan pidana
dalam pembentukan hukum adalah perbuatan yang berbahaya
bagi satu atau lebih anggota masyarakat dan bertindak
dengan suatu sanksi pidana terhadap hal itu adalah
efektif, disamping juga berguna dan perlu.”
Jika membandingkan rumusan Jean-Paul Brodeur dan
Geneviève Ouellet , Bemmelen dan Alida, maka akan terlihat
jelas bahwa tidak terdapat banyak perbedaan. Elemen
pokok dari kejahatan menurut ketiga sarjana tersebut
adalah adanya bahaya bagi anggota masyarakat. Elemen
lain seperti ketidaksusilaan, ketidaktenangan, harm,
dan damage pada dasarnya merupakan elemen turunan dari
bahaya perbuatan tersebut.
Michael J. Allen mempostulasikan pendapat yang menarik
dan berbeda dari Jean-Paul Brodeur dan Geneviève Ouellet,
Bemmelen dan Alida. Allen mendefinisikan “kejahatan
sebagai suatu perbuatan (atau kelalaian atau suatu
kondisi) yang melanggar hukum dan yang bisa dihukum
melalui prosedur peradilan pidana dengan konsekuensi
terkait, seperti putusan bersalah dan hukuman.”39 Allen38 J M. van Bemmelen, Criminoligie, leerboek der misdaadkunde, cet-4,
(Zwolle, 1958), hal 16 dalam Roeslan Saleh, op.cit., hal 80.
39 Michael J. Allen, Textbook on Criminal Law, edisi ke-9,(Newyork: Oxford University Press, 2007), hal 1.
Universitas Indonesia
25
menggunakan pendekatan definisi daripada teori.
Perbedaan yang menarik dari pendapatnya adalah bahwa
“ketika pembentuk undang-undang menentukan bahwa
perbuatan tertentu adalah kejahatan, sifat (nature) dari
perbuatan tersebut tidak berubah, namun konsekuensi
dari melakukan perbuatan tersebut yang berubah.”40
Contoh, jika A meninju muka B, maka A bersalah atas
kejahatan penganiayaan. Tindakan meninju tersebut juga
merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan bentuk
pelanggaran terhadap orang-perseorangan. Jika B,
digugat oleh P dan gugatannya dikabulkan, B harus
bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi.
Dalam skripsi ini, Penulis memakai pendekatan teori
dan definisi normatif. Penulis mengambil satu langkah
mundur sebelum suatu perbuatan dikriminalisasi. Dalam
konteks Skripsi ini, perbuatan yang dimaksud adalah
kartel. Alasan Penulis mengambil pendekatan ini adalah
karena kejahatan kartel sulit untuk dideteksi dan
sehingga sulit untuk diukur reaksi sosialnya. Berbeda
dengan kejahatan seperti pembunuhan yang menimbulkan
rasa jijik (disgust), kejahatan kartel merupakan
kejahatan yang bersifat white-collar crime. Selain itu,
senada dengan pendapat Jean-Paul Brodeur dan Geneviève Ouellet,
pembahasan dasar kriminalisasi kartel adalah untuk
meletakkan dasar normatif untuk kriminalisasi di masa
yang akan datang. Penentuan tingkat kejahatan dalam
40 Ibid.
Universitas Indonesia
26
kartel belum dibahas secara komprehensif, terutama di
Indonesia, sehingga diperlukan sebuah kajian untuk
mengupas subyek tersebut.
1.5 Metode Penelitian
Penelitian Skripsi ini merupakan penelitian hukum.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kepustakaan. Metode pendekatan analisis
data yang dipergunakan adalah metode analisis
kualitatif sehingga menghasilkan laporan yang bersifat
deskriptif analitis.41 Penelitian Skripsi ini menurut
bentuknya adalah penelitian prespkriptif,42 sedangkan
menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah
(problem-focused research).
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan
tersier. Data sekunder dan tersier digunakan untuk
memperoleh dan menjelaskan bahan hukum yang berkaitan
dengan pokok bahasan. Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari
41 Sri Mamudji et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UniversitasIndonesia,2005), hal 67.
42 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UIPress, 2005), hal. 10. Apabila suatu penelitian ditujukan untukmendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untukmengatasi masalah-masalah tertentu, maka penelitian tersebutdinamakan penelitian preskriptif.
Universitas Indonesia
27
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai
berikut.43
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang
mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan
perundang-undangan Indonesia, yaitu UU No. 5 tahun
1999 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat
kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat
membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan
bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori
para sarjana, putusan pengadilan, legislasi asing,
buku, penelusuran internet, artikel ilmiah,
jurnal, surat kabar, dan makalah.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan
hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedi,
atau kamus.
Terkait model pembanding, Penulis menggunakan
Regulatory Impact Assessment (2010) Selandia Baru tentang
dasar kriminalisasi kartel sebagai model pembanding
untuk dasar kriminalisasi kartel. Sementara itu,
Penulis menggunakan game theory of prisoner’s dilemma di
Amerika Serikat sebagai model pembanding untuk dasar
penentuan sanksi dan efektifitas serta efisiensi sanksi
atas kartel.
43 Ibid, hal. 32.
Universitas Indonesia
28
Alasan Penulis menggunakan Selandia Baru sebagai
model pembanding terkait isu dasar kriminalisasi kartel
adalah sebagai berikut. Pertama, kajian tentang dasar
kriminalisasi kartel dalam RIA Selandia Baru merupakan
salah satu kajian tentang dasar kriminalisasi terbaru,
yaitu pada awal tahun 2010.44 Kedua, kajian RIA
tersebut didasarkan pada kajian OECD tahun 2006 tentang
kartel yang merupakan rujukan yang cukup universal
(diterima dan dipraktikan banyak negara), terutama
karena laporan OECD tersebut merangkum praktik negara-
negara yang paling berkembang (advanced) dalam hal
dasar kriminalisasi kartel.45 Ketiga, kajian RIA
tersebut mengupas dasar kriminalisasi kartel secara
cukup komprehensif.
Alasan Penulis menggunakan Amerika Serikat sebagai
model pembanding terkait isu dasar penentuan sanksi dan
efektifitas serta efisiensi sanksi atas kartel adalah
sebagai berikut. Pertama, hukum persaingan usaha di
Amerika Serikat merupakan rezim hukum persaingan usaha
yang paling tua di dunia.46 Kedua, game theory of prisoner’s44 Manatu Ohanga, op.cit.
45 OECD 2006, Hard Core Cartels – Third Report on the Implementation of the1998 OECD Recommendation, dalam OECD Journal of Competition Law and Policy,Vol 8 no 1. Negara-negara berkembang yang dimaksud termasuk,Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Uni Eropa.
46 Di Amerika Serikat, hukum persaingan usaha termaktub dalamSherman Act yang dilegislasi pada tahun 1890 dan Clayton Act yangdilegislasi pada tahun 1914. Sementara di Uni Eropa, hukumpersaingan usaha baru dilegislasi pada tahun 1958 dalam Treaty ofRome. Di Kanada, hukum persaingan Usaha baru dilegislasi padatahun 1985 dalam Competition Act. Di Jepang, hukum persaingan usaha
Universitas Indonesia
29
dilemma berkembang relatif pesat di Amerika Serikat dan
terbukti cukup efektif dan efisien dalam mendeteksi,
menginvestigasi, menangkap, dan menghancurkan kartel.
Hal ini terbukti dari tingkat keberhasilan yang dicapai
oleh otoritas persaingan usaha Amerika Serikat, the
Antitrust Division, yaitu (i) kenaikan jumlah permohonan
amnesti dari korporasi yang diajukan kepada Antitrust
Division, (ii) jumlah sanksi denda terhadap kartel
terlapor meningkat pesat,47 (iii) peningkatan jumlah
denda yang didapatkan Antitrust Division dari USD 29 juta
per tahun (sebelum tahun 1997) menjadi USD 200 juta per
tahun (pada tahun 1997-1998), dan menjari USD 1,1
milyar pada tahun 1999.48 Bahkan melalui bukti-bukti
yang diajukan di pengadilan Amerika Serikat, seperti
terkait kasus F. Hoffman-La Roche tentang kartel penetapan
harga vitamin pada tahun 1999, Pengadilan Uni Eropa
baru dilegislasi pada tahun 1947 dalam Antimonopoly Act.
47 Gary R. Spratling, Asisten Deputi Attorney GeneralAntitrust Division, Deparment of Justice Amerika Serikat, MakingCompanies An Offer They Shouldn't Refuse: The Antitrust Division's Corporate LeniencyPolicy-An Update, dipresentasikan pada the Bar Association of the District ofColumbia's 35th Annual Symposium on Associations and Antitrust 3 (Feb. 16,1999)/ Lihat di http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/2247.pdf. (kunjungan terakhir 30Mei 2010).
48 Scott D. Hammond (2), Direktur Criminal EnforcementAntitrust Division, Department of Justice Amerika Serikat, Detectingand Deterring Cartel Activity Through An Effective Leniency Program,dipresentasikan pada the International Workshop on Cartels 10 (Nov. 21-22,2000). Lihat di http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/9928.pdf(kunjungan terakhir 30 Mei 2010).
Universitas Indonesia
30
dibantu untuk mendeteksi dan membuktikan kejahatan
kartel.49
1.6 Sistematika Penulisan
Dalam Bab I, Penulis akan menjabarkan tentang
permasalahan dan dilema dasar krimsinalisasi di
Indonesia, termasuk penyebab dari kesemrawutan hukum
pidana yang ada, dampak buruk dari kesemrawutan yang
ada. Selain itu, Bab ini juga menjelaskan secara lebih
khusus tentang permasalahan dan dilema dasar
kriminalisasi kartel dalam ranah hukum persaingan
usaha. Selanjutnya, Bab I akan menjelaskan tentang
tujuan umum pemidanaan dan apa tujuan pemidanaan kartel
di Indonesia.
Dalam Bab II, Penulis akan menjabarkan tentang
dasar kriminalisasi/tujuan pemidanaan suatu perbuatan.
Lebih spesifiknya, apa saja yang harus dipertimbangkan
seorang legislator atau lawmaker ketika menentukan
suatu perbuatan sebuah tindak pidana. Dalam Bab II,
juga akan dijelaskan tentang dilema dalam menentukan
kualifikasi/kriteria tindak pidana ketika ada
kepentingan-kepentingan yang bertentangan.
Dalam Bab III, Penulis akan menjabarkan tentang apa
yang dimaksud kartel, ciri-ciri kartel, dampak negatif
kartel, dan dasar kriminalisasi kartel. Penjelasan ini49 F. Hoffman-La Roche juga dihukum oleh otoritas persaingan
usaha Uni Eropa berdasarkan bukti-bukti yang digunakan olehAntitrust Division di pengadilan Amerika Serikat denganmenggunakan strategi prisoner’s dilemma.
Universitas Indonesia
31
akan didasarkan pada RIA Selandia Baru 2010 tentang
kriminalisasi kartel. Penulis akan menjabarkan dampak
buruk kartel dengan menggunakan pendekatan disiplin
ilmu hukum dan ekonomi.
Dalam Bab IV, Penulis akan menjabarkan tentang apa
yang dimaksud dengan strategi prisoner’s dilemma dan
bagaimana cara otoritas Amerika Serikat menerapkannya
terkait dengan dasar penentuan sanksi dan efektifitas
serta efisiensi sanksi atas kartel. Penulis akan
menguraikan kaitan antara penentuan sanksi pidana
penjara, pidana denda, dan/atau ganti rugi perdata
dengan prinsip ultimum remedium. Selanjutnya, Penulis
akan menjabarkan kerancuan dan/atau absurditas
penentuan sanksi terhadap kartel berdasarkan UU No.
5/1999. Pada akhirnya, Penulis akan membahas tentang
kemungkinan penerapan strategi prisoner’s dilemma di
Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
penerapan sanksi atas kartel.
Dalam Bab V, Penulis akan menjabarkan tentang
simpulan dasar kriminalisasi kartel dan metode yang
efektif untuk menangani kartel. Selanjutnya, Penulis
akan memaparkan saran yang konstruktif bagi pihak
legislator dalam perumusan dasar kriminalisasi kartel,
penentuan sanksi atas kartel, dan kemungkinan
menerapkan strategi prisoner’s dilemma di Indonesia untuk
meningkatkan efek jera dari sanksi tersebut.
Universitas Indonesia
33
BAB IIDASAR PENGKRIMINALISASIAN SUATU PERBUATAN
Jawaban terhadap pertanyaan apa itu kejahatan
(crime) mungkin terkesan sederhana, namun pergelutan
dalam diskursus ini merupakan yang tersulit dalam
disiplin hukum pidana. Perbuatan pidana atau bukan
umumnya bisa dilihat dari ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan atau hukum positif. Misalnya, pasal
338 KUHP melarang pembunuhan. Namun, yang ingin dibahas
penulis dalam bab ini adalah tentang dasar
kriminalisasi yang merupakan satu langkah sebelum
perumusan ketentuan pidana tersebut, contohnya mengapa
pembunuhan dikriminalisasi, bukan pertanyaan mengenai
cara mengidentifikasi suatu perbuatan pidana dalam
hukum positif atau undang-undang.50 Oleh karena itu,
pembahasan Bab I dimulai dari isu paling mendasar yaitu
kebijakan kriminal (criminal policy) dan kebijakan hukum
pidana (penal policy). Kemudian, setelah memaparkan
kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, Penulis
akan membahas kriteria penentuan suatu perbuatan
sebagai tindak pidana. Selanjutnya, akan dibahas tujuan
dan fungsi hukum pidana
50 Dalam kutipan arogannya advokat klasik Inggris: “The primarydifference between a lawyer and a commoner is everyone may know what the law is, butlawyer knows where to look for it.”
Universitas Indonesia
34
2.1 Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dan
Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)
2.1.1 Arti kebijakan criminal (criminal policy)
dan kebijakan hukum pidana (penal policy) dan
hubungan antara keduanya
Prof Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai
kebijakan kriminal (criminal policy), yaitu:51
1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan
metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap
pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari
aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara
kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari
Jorgen Jepsen) ialah keseluruhan kebijakan, yang
dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-
badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan
norma-norma sentral dari masyarakat.
Definisi ini sesuai dengan pendapan Marc Ancel
yang merumuskan politik kriminal sebagai “the rational
organization of the control of crime by society”.52 Sementara G.
Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa secara umum“Criminal
51 Barda Nawawi, op.cit., hal 1.52 Marc Ancel, Social Defence, 1965, hal 209 dalam Ibid, hal 2.
Universitas Indonesia
35
policy is the rational organization of the social reaction to crime”.53
Hoefnagels mengemukakan bahwa secara khusus:54
1. Criminal policy is the science of responses;
2. Criminal policy is the science of crime prevention;
3. Criminal policy is a policy of designating human behavior as
crime;
4. Criminal policy is a rational total of the responses to crime.
Perumusan tujuan kebijakan kriminal (criminal policy)
dinyatakan dalam salah satu laporan UNAFEI di Tokyo
tahun 1973 sebagai berikut:55
“Most of group members agreed some discussion that “protection
of the society” could be accepted as the final goal of criminal policy,
although not the ultimate aim of society, which might perhaps be
described by terms like “happiness of citizens”, a”wholesome and
cultural living”, “social welfare” or “equality”
Singkatnya, kebijakan atau upaya penganggulangan
kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral
dari upaya perlindungan masyarakat (social defense) dan
upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).
Oleh karena itu, tujuan akhir dari kebijakan kriminal
53 G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, 1969, hal 57dalam Ibid.
54 Ibid, hal 57, 99, 100.
55 Summart Report, Resource Material Series No. 7, UNAGERI, 1974,hal 95.
Universitas Indonesia
36
(criminal policy) ialah “perlindungan masyarakat untuk
mencapai kesejahteraan rakyat”
Sementara itu, yang dimaksud kebijakan hukum
pidana (penal policy), menurut Prof. Sudarto, adalah:
1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang
baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada
suatu saat.56
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang
berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan
yang dikehendaki yang diperkirakan bisa
digunakan untuk mengekspresikan apa yang
terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai
apa yang dicita-citakan.57
Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal
dengan menggunakan penal policy adalah masalah penentuan:
1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak
pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau
dikenakan kepada si pelanggar.
Secara skematis, hubungan politik kriminal (social
policy) dengan kebijakan pidana (criminal policy) dan
56 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981), hal159 dalam Badar Nawawi, op.cit., hal 24.
57 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Bandung:Sinar Baru, 1983) hal 20 dalam Barda Nawawi, Ibid, hal 25.
Universitas Indonesia
37
kebijakan hukum pidana (penal policy) dapat digambarkan
sebagai berikut.58
Bagan 1
Alasan mengapa criminal policy dibagi menjadi penal
dan non-penal adalah karena tidak semua kebijakan
kriminal diwadahkan dalam kebijakan hukum pidana
terutama terkait dengan sanksi pidana. Senada dengan
pernyataan di atas. G. Peter Hoefnagels juga
mengemukakan:
“Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the
law enforcement policy… The legislative and enforcement policy is
in turn part of social policy.”
Bagan 2
58 Barda Nawawi, op.cit., hal 3.
Universitas Indonesia
Social Defence Policy
38
2.1.2 Manfaat perumusan kebijakan pidana
Salah satu tujuan dari social policy adalah
kesejahteraan ekonomi (social welfare policy). Kejahatan
dipandang sebagai suatu perbuatan yang menghilangkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga criminal policy
berorientasi pada tujuan yang sama dengan social welfare
policy yaitu, salah satunya, kesejahteraan ekonomi. Jika
merujuk pada bagan 1 di atas, maka perbedaan social
welfare policy dan criminal policy adalah perumusan social welfare
policy bersifat positif dalam arti tindakan positif
diperlukan untuk menciptakan atau meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Tanpa tindakan positif
tersebut, maka kesejahteraan rakyat tidak akan
Universitas Indonesia
Administrative and civil law
39
tercapai. Sementara itu, perumusan criminal policy bersifat
negatif dalam arti tindakan (kejahatan) tertentu harus
dicegah atau dihalangi supaya kesejahteraan masyarakat
bisa tercipta atau ditingkatkan. Tanpa tindakan
(kejahatan) tersebut, maka kesejahteraan masyarakat
akan tercapai.
Kesejahteraan ekonomi sebagai salah satu tujuan
dari criminal policy juga dikemukakan dalam Deklarasi
Caracas yang dihasilkan Kongres PBB ke-6 tahun 1960
yang menyebutkan:59
“Crime prevention and criminal justice should be considered in the
context of economic development, political system, social and
cultural values and social change, as well as in the context of the
new international economic order (Deklarasi No. 2)”.
Selanjutnya dalam Guiding Principles for Crime Prevention
and Criminal Justice in the Context of Development and a New
International Economic Order yang juga dihasilkan oleh
Kongres PBB ke-7 di Milan, antara lain dinyatakan
( dalam sub B mengenai “National Development and the prevention
of crime”).60
“Crime prevention as part of social policy
59 Sixth UN Congress, Report, 1981, hal 3.
60 United Nation, Guiding Principles for Crime Prevention and CriminalJustice in the Context of Development and a New international Economic Order, UNDepartment of Public Information, Agustus 1988, hal 9-10.
Universitas Indonesia
40
21. The criminal justice system, besides being an instrument to
effect control and deterrence, should also contribute to the
objective of maintaining peace and order for equitable social and
economic development, redressing inequalities and protecting
human rights.”
Kemudian, anggota Kongres ke-5 tahun 1975 di
Geneva meminta perhatian, antara lain, terhadap:
“Crime as business, yaitu kejahatan yang bertujuan
mendapat keuntungan material melalui kegiatan
dalam bisnis atau industry, yang pada umumnya
dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh
mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam
masyarakat, termasuk dalam kejahatan ini antara
lain yang berhubungan dengan pencemaran
lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang
perbankan, di samping kejahatan-kejahatan lainnya
yang biasa dikenal dengan “organized crime”, “white
collar crime” dan korupsi.”
Selanjutnya, dalam Kongres PBB ke-7 tahun 1985,
antara lain, dimintakan perhatian terhadap kejahatan-
kejahatan tertentu yang dipandang membahayakan seperti
“economic crime” khususnya yang berhubungan dengan
masalah pelanggaran terhadap ketentuan/persyaratan
barang dan jasa bagi para konsumen (offences against the
provision of goods and services to consumers).
Universitas Indonesia
41
Senada dengan pendapat di atas, Ted Honderich
menyatakan bahwa pendekatan rasional pragmatis berarti
mengandung pula pendekatan kemanfaatan/kegunaan
(utilitas).61 Sehubungan dengan ini juga, Jeremy
Bentham pernah menyatakan bahwa pidana janganlah
diterapkan/digunakan apabila “groundless, needless,
unprofitable, or inefficacious”.62
2.2 Kriteria penentuan suatu perbuatan sebagai
tindak pidana/kejahatan (crime)
Mengenai kriteria penentuan suatu perbuatan sebagai
kejahatan, Professor Ashworth berpendapat bahwa
“kesempatan politik dan kekuasaan, dimana keduanya
terkait dengan kultur politik suatu negara yang sedang
berlangsung merupakan faktor penentu utama.”63
Pendekatan ini bersifat lebih pragmatis. Secara umum,
ada dua pertanyaan yang penting dalam kaitannya dengan
kriteria tersebut.64 Pertama, apakah perbuatan tersebut
mempunyai dampak buruk berupa rasa sakit (harmful)
61 Barda Nawawi, op.cit., hal 35.
62 Ibid.
63 A. Ashworth, Principles of Criminal Law, edisi ke-2, (Oxford:Clarendon, 1995), hal 55.
64 Mike Molan, Denis Lanser, dan Duncan Bloy, Principles of CriminalLaw, edisi ke-4, (Britania Raya: Cavendish Publishing, 2000), hal12.
Universitas Indonesia
42
kepada individu atau masyarakat? Kedua, apakah
perbuatan tersebut immoral?
Jika jawaban kepada kedua pertanyaan tersebut
adalah iya, maka perbuatan tersebut dianggap secara
prima facie pantas untuk dikriminalisasikan. Pendekatan
klasik ini masih terlalu sumir atau simplistik karena
ada perbuatan yang immoral dan harmful namun belum
dikriminalisasi (misalnya, kumpul kebo). Sementara itu,
ada perbuatan yang tidak immoral maupun harmful, namun
dikriminalisasikan, misalnya tidak/lupa memakai seat belt
dan kejahatan yang tidak ada korbannya (victimless crimes).
Hukum tidak bisa mengkriminalisasikan semua
perbuatan immoral karena:65
a. Kesulitan pembuktian (kebanyakan perbuatan
terjadi/dilakukan dalam ruang privat dan tidak
terdapat saksi yang independen).
b. Kesulitan dalam pendefinisian (contohnya, seorang
suami yang ditinggalkan oleh istrinya bertahun
lamanya dan sekarang suami tersebut sudah menikah
lagi. Jika suami tersebut melakukan hubungan intim
(seks), apakah ia bisa dihukum atas kejahatan
perzinahan?).
c. Aturan tentang moralitas dalam situasi tertentu
sangat sulit untuk diterapkan tanpa melanggar hak-
hak individu akan privasi).
65 Id, hal 13.
Universitas Indonesia
43
d. Sistem hukum Eropa Kontinental (civil law) dalam
beberapa kasus menyediakan kompensasi yang cukup
bagi pihak yang dirugikan oleh perbuatan tertentu
(contoh, hak dari istri yang ditinggalkan).
e. Bagaimana cara menentukan “pendapat moral” yang
ada sementara terdapat perbedaan-perbedaan nilai
moral yang mendalam dan tajam dalam masyarakat
modern?
Lord Devlin berargumen bahwa suatu perbuatan harus
dikriminalisasi jika perbuatan tersebut menimbulkan
“kebencian/kejijikan yang mendalam” (deep disgust)
terhadap individu yang berpikiran benar (right-minded
individual).66 Namun, HLA Hart mengkritik pendapat ini
dengan menyatakan: bagaimana jika orang yang berpikiran
benar tersebut mendasarkan pikirannya pada
ketidaktahuan (ignorance), takhayul, atau
kesalahpahaman?67 Jika pendapat Lord Devlin yang diikuti,
maka kekuasaan pembuat hukum akan didelegasikan kepada
para pemilik surat kabar atau tabloid dan ini merupakan
hal yang sangat buruk. Sebaliknya, jika pembuat hukum
merumuskan hukum tanpa menilik nilai-nilai individu
yang berpikiran benar, hukum akan kehilangan kewibawaan
dan penghormatan dari masyarakat luas dan ini juga
merupakan hal yang sangat buruk.68
66 P. Devlin , The Enforcement of Morals, (Oxford: OUP, 1965).
67 HLA Hart, Law, Liberty and Morality, (Oxford: OUP, 1963).
68 Mike Molan, Denis Lanser, dan Duncan Bloy, op.cit., hal 13.
Universitas Indonesia
44
Pendapat Herbert Packer adalah pendapat yang mungkin
paling berguna dan praktis dalam menentukan perbuatan
apa yang seharusnya dikriminalisasi. Packer menyarankan
beberapa kriteria selain immoralitas dan rasa sakit
(harm) dan kerusakan (damage) yang ditujukan kepada
seseorang atau barang:69
1. Mayoritas masyarakat tersebut memandang perbuatan
tersebut sebagai ancaman sosial.
2. Perbuatan tersebut tidak pernah
ditoleransi/diizinkan oleh sebagian besar kalangan
masyarakat.
3. Menekan/mengisolasi perbuatan tersebut tidak akan
menghalangi perbuatan yang diinginkan masyarakat
luas (socially desirable conduct).
4. Masalah tersebut bisa ditangani dengan
implementasi hukum yang adil dan non-
diskriminatif.
5. Usaha untuk mengontrol perbuatan tersebut tidak
akan mengekspos sistem peradilan pidana kepada
kekangan kualitatif atau kuantitatif yang besar
(severe qualitative or quantitative strains).
6. Tidak ada alternatif lain yang masuk akal selain
sanksi pidana untuk mengatasi masalah tersebut.
7. Biaya untuk penegakkan hukumnya tidak mahal/besar.
69 Herbert Packer, The Limits of the Criminal Sanction, (CA: StanfordUP, 1968).
Universitas Indonesia
45
2.3 Tujuan Hukum Pidana
Prof. Mr. Roeslan Saleh berpendapat bahwa untuk
menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana
maka harus terlebih dahulu dipersoalkan mengenai tujuan
apakah pada umumnya yang akan dicapai pembentuk undang-
undang dengan menentukan suatu perbuatan sebagai
perbuatan pidana.70 Dengan kata lain, apakah yang ingin
dicapai dengan pidana? Beberapa tujuan yang ingin
dicapai hukum pidana adalah pembalasan, prevensi umum,
prevensi khusus, menegakkan hukum, menyelesaikan
konflik-konflik, membatasi dan menghindarkan “main
hakim sendiri”. D. Simons, dalam buku pelajaran hukum
pidana paragraf 18 dari Bagian Umumnya dan paragraf 326
dari Bagian Khususnya menyebutkan, bahwa “pada dasarnya
tiap kepentingan dari individu mendapat perhatian,
untuk jika perlu dilindungi dengan hukum pidana, yaitu
sejauh kepentingan itu secara langsung atau tidak
langsung juga mempunyai arti bagi masyarakat”.
Gulden regel
Kepentingan manusia yang berbeda-beda menyebabkan
banyaknya konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini
harus diselesaikan dengan, salah satu caranya,
menyepakati nilai yang dianggap jahat atau tidak. Salah
satu tujuan pemidanaan/kriminalisasi adalah sebagai
wadah konsensus dari nilai kejahatan. Tanpa wadah70 Roeslan Saleh, op.cit., hal 73.
Universitas Indonesia
46
konsensus ini, ukuran kejahatan menjadi sangat kabur
dan/atau ambigu. Walaupun kesepakatan ini mungkin tidak
melahirkan penentuan nilai kejahatan yang
baik/sempurna, tanpa kesepakatan ini penentuan nilai
kejahatan menjadi jauh lebih kabur dan/atau ambigu.
Kesepakatan atas nilai tersebut, seperti saling
menghormati, kewajiban moral, keadilan dan patut
dihormatinya aturan-aturan tertentu, dinamakan asas
gulden regel.71
Asas gulden regel memaksa anggota masyarakat untuk
menimbang kepentingan sendiri dan kepentingan orang
lain dengan timbangan yang sama. Bagaimana seseorang
dapat meyakinkan orang lain bahwa justru kepentingannya
sendiri yang harus ditimbang lebih berat daripada orang
lain, jika pada kenyataannya kepentingan-kepentingan
itu adalah sama? Anggapan yang ada dalam penerapan
aturan itu adalah bahwa ada kesediaan untuk berunding
yang menimbulkan secara langsung dasar untuk
diadakannya beberapa penentuan dapat dipidananya suatu
perbuatan.
Menghindari main hakim sendiri
Dalam realitanya, masyarakat mempunyai nilai yang
berbeda-beda. Jika nilai tersebut dilanggar oleh
seseorang dalam masyarakat tersebut maupun dari luar
71 Langmeyer, Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts, 2edruk, hal 207 dalam Roeslan Saleh, op.cit., hal 81.
Universitas Indonesia
47
masyarakat tersebut, maka akan muncul perasaan untuk
menghakimi dan menghukum. Oleh karena tidak adanya
kesepakatan penentuan nilai kejahatan, masyarakat akan
cenderung menerapkan sanksi yang dianggap pantas
terhadap suatu perbuatan yang dianggap melanggar nilai
tersebut. Menurut Penulis, salah satu tujuan yang ingin
dicapai pidana adalah untuk menghindari “main hakim
sendiri.” Senada dengan pendapat tersebut, Prof Roeslan
Saleh menyatakan “Dalam kejadian-kejadian dimana
penyelesaian terhadap konflik yang ditimbulkan oleh
pembuat itu adalah semata-mata menegaskan adanya pidana
oleh karena dia, dengan perbuatan itu telah berbuat
lain daripada yang diharapkan dari dia berdasarkan
larangan yang telah diadakan. Pidana itu bertujuan
untuk menghindarkan ‘main hakim sendiri’ yang mungkin
akan dilakukan oleh pihak yang dirugikan dan dari semua
orang yang berkeinginan agar ketentuan-ketentuan itu
dipertahankan.”72 Prof Roeslan memisahkan antara
kejahatan yang berat (misalnya pemerkosaan) dan ringan
(misalnya penyelewengan pajak dan pelanggaran hak
cipta). Kejahatan yang berat cenderung memerlukan
sanksi pidana. Contoh, anggota masyarakat yang
mengetahui bahwa seorang yang mabuk dan bejat yang
memperkosa anak perempuannya tidak dipidana, maka bapak
anak perempuan tersebut pasti akan menghukum pembunuh
itu sendiri.
72 Roeslan Saleh, op.cit., hal 84.
Universitas Indonesia
48
2.4 Fungsi sanksi pidana
Secara umum, fungsi hukum pidana adalah sebagai
kontrol sosial dan moral. Pendapat senada juga
diartikulasikan oleh Mardjono Reksodiputro.73 Hukum
pidana merupakan perwujudan aturan-aturan dari kontrol
sosial dalam sebuah masyarakat. Cara menentukan
aturan-aturan dari kontrol sosial tersebut adalah bahwa
fungsi hukum pidana adalah “untuk melindungi ketertiban
umum dan nilai kepatutan, untuk melindungi masyarakat
dari perbuatan yang dianggap ofensif atau berbahaya dan
untuk menyediakan perlindungan yang cukup melawan
eksploitasi atau korupsi atas orang lain, terutama
kalangan yang rentan karena usia yang muda, lemah
secara fisik maupun psikis, atau tidak berpengalaman,
atau mempunyai ketergantungan fisik, jabatan, atau73 Menurutnya, konsep ke-1 RUU KUHPidana yang diajukan pada
tahun 1993 juga memperhatikan perlindungan terhadap hak asasiwarga masyarakat, dengan didukung oleh tiga prinsip yaitu sebagaiberikut:hukum pidana (juga) dipergunakan untuk menegaskan atau menegakkankembali nilai – nilai sosial dasar (fundamental social values)perilaku hidup bermasyarakat (dalam Negara Kesatuan RepublikIndonesia, yang dijiwai oleh falsafah dan ideologi negaraPancasila);
a. hukum pidana (sedapat mungkin) hanya dipergunakan dalamkeadaan di mana cara lain melakukan pengendalian sosial(social control) tidak (belum) dapat diharapkankeefektifannya; dan
b. hukum pidana (yang telah mempergunakan kedua pembatasan(a dan b diatas) harus diterapkan dengan cara seminimalmungkin mengganggu hak dan kebebasan individu, tanpamengurangi perlunya juga perlindungan terhadapkepentingan kolektifitas dalam masyarakat demokratikyang modern.
Universitas Indonesia
49
ekonomi secara khusus. Bukan tugas hukum untuk
mengintervensi ruang hidup privat masyarakat, atau
untuk memaksakan penegakkan pola prilaku tertentu.” 74
Sanksi pidana bertujuan untuk menghukum perbuatan
salah yang mengancam nilai-nilai fundamental yang
merupakan pondasi suatu masyarakat.75 Perbuatan mencuri
atau menganiaya menyebabkan rasa sakit (harm) dan
kerusakan (damage) terhadap seorang individu dan pada
saat yang sama menyebabkan rasa sakit (harm) dan
kerusakan (damage) kepada masyarakat luas karena
perbuatan tersebut mengancam keamanan dan kenyamanan
masyarakat.76 Muladi menyatakan karena tujuannya
bersifat integratif maka perangkat tujuan pemidanaannya
adalah: (a) pencegahan umum dan khusus, (b)
perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas
masyarakat, dan (d) pengimbalan/pengimbangan.
Lebih khususnya, beberapa fungsi hukum pidana
adalah retribusi, deteren/efek jera, pelumpuhan
(incapacitation), dan rehabilitasi, dan restoratif.
2.3.1 Retribusi
Tujuan utama dari hukuman adalah sebagai retribusi.
Hukuman diberikan kepada pelanggar hukum karena hal
74 The Wolfenden Committee, Report of the Committee of HomosexualOffences and Prostitution (1957), Cmnd 247, paragraf 13 dan 14.
75 Michael J. Allen, op.cit., hal 3.
76 Ibid.
Universitas Indonesia
50
tersebut pantas atas pelanggarannya terhadap hukum. Hal
ini dinyatakan oleh Stephen “Hukuman berdasarkan hukum
menciptakan kepastian dan pembenaran (justification) korban
kejahatan atas rasa benci mereka atas kejahatan yang
dilakukan, dan mendasarkan hukuman tersebut pada moral
dan hal yang diterima khalayak ramai daripada hukuman
berdasarkan hati nurani. Oleh karena itu, hukum pidana
membenarkan secara moral perasaan benci terhadap
kejahatan dan sekaligus membenarkan sentimen tersebut
dengan menjatuhkan hukum terhadap penjahat tersebut.”77
Dengan kata lain, retribusi mencerminkan keinginan
masyarakat untuk membalas dendam. Ketika orang-orang
berkumpul dalam sebuah masyarakat yang diatur oleh
hukum, mereka melepaskan haknya untuk membalas dendam
atas rasa sakit (harm) dan kerusakan (damage) yang
dilakukan kepada mereka sebagai ganti atas perlindungan
yang hukum berikan kepada mereka. Senada dengan
pendapat di atas, H. Cross menyatakan “masyarakat
menuntut hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan
diserahkan oleh setiap individu, dan sebagai gantinya
hukum akan memberikan perlindungan. Perlindungan hukum
ini efektif hanya jika pelanggaran hukum/kejahatan itu
dihukum. Keseimbangan ini tercapai dengan meletakkan
kewajiban moral kepada masyarakat untuk menghukum
77 Stephen, A History of Criminal Law of England, (1883), paragraf 81-82.
Universitas Indonesia
51
kejahatan karena ada kewajiban moral dari setiap
individu untuk tidak melanggar hukum.”78
Balas dendam merupakan salah satu aspek dari
retribusi. Elemen lain adalah kecaman publik
(denunciation).79 Penghukuman menunjukkan ketidaksetujuan
masyarakat atas perbuatan jahat tertentu dan
mengafirmasi nilai-nilai hukum pidana yang telah
ditentukan. Namun, hukuman yang dijatuhkan bukan
merupakan balas dendam yang membabi-buta. Hukuman
tersebut harus beralasan (reasoned) dan masuk akal
(reasonable). Sesuai dengan pendapat Immanuel Kant,
seseorang yang melakukan kejahatan telah mengambil
keuntungan secara tidak adil dari anggota masyarakat
lainnya sehingga hukuman menetralkan keuntungan yang
tidak adil itu (terutama ketika pengadilan
memerintahkan penyitaan, restitusi, atau kompensasi).80
Hukuman yang pantas untuk seorang penjahat, harus
terkait dengan rasa sakit (harm) dan kerusakan
(damage) yang telah disebabkan olehnya. Selain itu,
hukuman tersebut masuk akal hanya jika dijatuhkan
secara proporsional.
2.3.2 Deteren atau efek jera
78 H. Cross, A Theory of Criminal Justice, (1979), paragraf 19-20.
79 Michael J. Allen, op.cit., hal 4.
80 Ibid.
Universitas Indonesia
52
Fungsi kedua dari hukuman adalah deteren/efek jera,
baik efek jera yang khusus (misalnya, memaksa penjahat
untuk tidak mengulangi kejahatannya di masa yang akan
datang) maupun efek jera yang umum (misalnya
mengingatkan calon pelaku kejahatan untuk tidak
melakukan kejahatan tersebut dengan mencontohkan
akibat/hukuman yang diterima oleh pelaku kejahatan
tersebut). Kesulitannya adalah beberapa pelaku
kejahatan mungkin tidak akan mengulangi kejahatannya
walaupun mereka tidak akan tertangkap lagi atau
dihukum, sementara pelaku kejahatan lain tidak akan
mengulangi kejahatan hanya jika hukuman begitu berat
dan bahkan di luar batas proporsional terhadap
kejahatan tersebut. Hukuman merupakan suatu keharusan
supaya hukum tidak kehilangan kekuatan memaksanya.
Masalah apakah seseorang lebih takut akan pemaksaan
itu, tergantung pada beberapa faktor. Packer menyatakan
bahwa “fungsi deteren dari hukum pidana berlaku efektif
kepada individu yang masih dipengaruhi oleh lingkungan
sosialnya sehari-hari. Fungsi deteren tidak akan
mengancam individu-individu yang menyedihkan dan tidak
mempunyai harapan lagi dalam hidupnya. Hukum tidak akan
memperbaiki moral orang-orang yang sistem nilainya
sudah ditutup untuk modifikasi, baik secara psikologis
maupun secara kultural.”81 Oleh karena itu, fungsi
deteren hukum pidana itu bersifat terbatas.
81 H.Packer, The Limits of the Criminal Sanction, (1968), hal 45.
Universitas Indonesia
53
2.3.3 Pelumpuhan (incapacitation)
Fungsi hukum pidana yang ketiga adalah pelumpuhan
(incapacitation). Jika seorang pelaku kejahatan dipenjara,
maka masyarakat luas atau publik akan dilindungi dari
kejahatan lain yang mungkin dilakukannya karena pelaku
kejahatan tersebut berada di dalam penjara. Fungsi
pelumpuhan ini sama dengan fungsi perlindungan
masyarakat.
2.3.4 Rehabilitasi
Pada dasarnya fungsi rehabilitasi hukum pidana melihat
bahwa pelaku kejahatan adalah orang sakit, sehingga
perlu disembuhkan. Penyakit ini bisa disembuhkan dengan
rehabilitasi melalui hukuman penjara, di mana pelaku
kejahatan tersebut diajarkan disiplin, moral, tingkah
laku yang diterima dalam masyarakat. Pada gilirannya,
pelaku kejahatan tersebut bisa dikembalikan ke dalam
masyarakat dengan fungsi yang baik. Disiplin ilmu
penologi pra-1960 berkutat pada ide tentang
rehabilitasi.82 Hukuman percobaan diperkenalkan untuk
memungkinkan ide rehabilitasi tersebut. Ide
rehabilitasi ini juga terdapat dalam Prison Rules 1964
Amerika Serikat yang menyatakan “tujuan dari pelatihan
dan perlakuan terhadap tahanan penjara adalah untuk
82 Michael J. Allen, op.cit., hal 5.
Universitas Indonesia
54
mendorong dan membantu mereka untuk meraih kehidupan
yang baik dan berguna.”
2.3.5 Restoratif
Menurut Penulis, perbedaan utama fungsi hukum
pidana dalam arti rehabilitasi dan restoratif adalah
sebagai berikut. Fungsi rehabilitasi menekankan pada
“penyembuhan” penjahat dari penyakit. Jadi,
penekanannya ada di penjahat sebagai subyek atau aktor.
Fungsi restoratif menekankan pada “penyembuhan” seluruh
dampak yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan yang
mencakup (i) harm dan damage yang ditimbulkan
kejahatan tersebut, (ii) subyek atau pelaku kejahatan,
(iii) obyek atau korban kejahatan (keluarga korban yang
dibunuh atau korban pemerkosaan, dan (iv) rasa tenteram
atau damai masyarakat.
Fungsi restoratif hukum pidana adalah sebuah konsep
pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan
pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan
masyarakat dan korban yang merasa tersisihkan dengan
mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana
yang ada pada saat ini.83 George Rizer menyatakan bahwa:
“Restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing
and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by
educational, legal, social work, and counseling professionals and
83 Eva Achjani Zulfa, op.cit., hal 14.
Universitas Indonesia
55
community groups.84 Restorative justice is a value-based approach to
responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the
person harmed, the person causing harm, and the affected community.85
Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu
paradigma baru yang dapat dipakai sebagai bingkai dari
strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan
menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan
pidana yang ada pada saat ini.86 Dasar pertimbangan
filosofis dari mekanisme ini adalah untuk mengurangi
dampak buruk dari stigmatisasi yang dilakukan oleh
masyarakat kepada seorang pelaku tindak pidana yang
kemudian diberi label narapidana.87
Arti leksikal dari kata restoratif (yang berasal
dari kata restore) adalah mengembalikan keadaan yang
rusak akibat kejahatan pada keadaan/kondisi semula.
Pendapat penulis terkait dengan fungsi restoratif hukum
pidana adalah apa nilai moral maupun praktis dari
mengembalikan keadaan yang rusak akibat kejahatan
kepada keadaaan/kondisi semula? Bukankah waktu tetap
berjalan? Bayangkan jika terdapat suatu keadaan A yang
seharusnya berada dalam titik waktu T (masa lampau),
84 George Rizer, Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) seperti dikutip dalamEva Achjani Zulfa, ibid, hal 14.
85 Ibid.
86 Eva Achjani Zulfa,op.cit., hal 15.
87 Ibid. hal 17.
Universitas Indonesia
56
namun rusak akibat kejahatan tertentu. Apakah tepat,
pada titik waktu S (masa sekarang), untuk mengembalikan
keadaan yang ada yang rusak (B) kepada keadaan yang
seharusnya ada (A)? Kurun waktu yang hilang antara T
sampai dengan S juga harusnya dihitung dalam fungsi
restoratif hukum pidana. Dalam istilah ekonomi, konsep
tersebut dinamakan opportunity cost, yaitu kesempatan yang
hilang akibat keadaan yang tidak ada. Korban kejahatan
banyak kehilangan waktu, tenaga (emosi dan fisik),
uang, dan rasa percaya akibat kurun waktu T sampai
dengan S, sehingga untuk mengembalikan keadaan yang ada
ke keadaan A memosisikan korban kejahatan kepada titik
waktu T, padahal korban tersebut hidup pada titik waktu
S. Jurang waktu ini merupakan suatu faktor yang harus
dipertimbangkan dalam fungsi restoratif hukum pidana.
Universitas Indonesia
57
BAB IIIPENGERTIAN KARTEL DAN DASAR KRIMINALISASI KARTEL
3.1 Pengertian kartel secara umum
Secara umum, kartel terbentuk ketika pelaku usaha
sepakat dengan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak
bersaing dengan satu sama lain. Struktur pasar yang
kompetitif, dimana pelaku usaha yang berusaha di dalam
pasar tersebut jumlahnya banyak, serta tidak ada
hambatan bagi pelaku usaha untuk masuk kedalam pasar,
membuat setiap pelaku usaha yang ada di dalam pasar
tidak mampu untuk menyetir harga sesuai dengan
keinginannya.88 Pelaku usaha hanya menerima harga yang
sudah ditentukan oleh pasar dan akan berusaha untuk
berproduksi secara maksimal supaya bisa mencapai suatu
tingkat produksi yang efesien.
Praktek kartel merupakan salah satu strategi yang
diterapkan diantara pelaku usaha untuk dapat
mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi
mereka. Asumsinya adalah jika produksi mereka di dalam
pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap produk
mereka di dalam pasar tetap, maka harga produk tersebut
akan naik. Sebaliknya, jika produk mereka melimpah di
88 Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, et.al., HukumPersaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, (Indonesia: DeutscheGesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009), hal.107.
Universitas Indonesia
58
dalam pasar, harga produk tersebut akan turun. Oleh
karena itu, pelaku usaha berusaha membentuk suatu
kerjasama horizontal untuk mempengaruhi harga dengan
mengontrol (mengurangi) jumlah produksi dan/atau
pemasaran (penjualan) barang dan/atau jasa.
Membanjirnya pasokan dari suatu produk tertentu di
dalam suatu pasar, dapat membuat harga dari produk
tersebut di pasar menjadi lebih murah, dimana kondisi
ini akan menguntungkan bagi konsumen, tetapi tidak
sebaliknya bagi pelaku usaha (produsen atau penjual),
karena semakin murahnya harga produk mereka di pasar,
membuat keuntungan yang akan diperoleh oleh pelaku
usaha tersebut menjadi berkurang.
Agar harga produk di pasar tidak jatuh dan harga
produk dapat memberikan marjin keuntungan yang
sebesar-besarnya bagi pelaku usaha, pelaku usaha
membuat perjanjian di antara mereka untuk mengatur
mengenai jumlah produksi sehingga jumlah produksi
mereka di pasar tidak berlebih. Tujuannya adalah agar
membuat harga produk mereka di pasar tidak menjadi
lebih murah. Tujuan paling utama adalah untuk mengeruk
keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengurangi
jumlah produk mereka secara signifikan di pasar,
sehingga terjadi kelangkaan produk tersebut di pasar,
yang mengakibatkan konsumen harus mengeluarkan biaya
yang lebih untuk dapat membeli produk pelaku usaha
tersebut di pasar, atau dapat dikatakan tujuan utama
Universitas Indonesia
59
dari praktek kartel adalah untuk mengeruk sebanyak
mungkin surplus konsumen ke produsen. Oleh karena
kartel menukar kompetisi dengan tindakan-tindakan yang
kolutif diantara pesaing, maka dilarang dalam hukum
persaingan usaha.89
Pada umumnya terdapat beberapa karakteristik dari
kartel.90 Pertama, terdapat konspirasi antara beberapa
pelaku usaha. Kedua, melakukan penetapan harga. Ketiga,
agar penetapan harga dapat efektif, maka dilakukan pula
alokasi konsumen atau produksi atau wilayah. Keempat,
adanya perbedaan kepentingan diantara pelaku usaha
misalnya karena perbedaan biaya. Tidak semua perjanjian
kartel dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat,
seperti misalnya perjanjian kartel dalam bentuk
mengisyaratkan untuk produk-produk tertentu harus
memenuhi syarat-syarat tertentu yang bertujuan untuk
melindungi konsumen dari produk yang tidak layak atau
dapat membahayakan keselamatan konsumen dan tujuannnya
tidak menghambat persaingan.91
3.2 Pengertian kartel berdasarkan unsur Pasal 11 UU
No.5/1999
Terkait definisi kartel, Pasal 11 UU No. 5 /1999
menyatakan:
89 William R. Andersen and C. Paul Rogers III, Antitrust Law: Policyand Practice, 3rd ed. (Mattew Bender, 1999) p.349.
90 Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, op.cit, hal 106.
91 Ibid, hal 107.
Universitas Indonesia
60
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan
pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk
mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan
atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat.”
Uraian unsur pasal 11 UU No.5/1999 adalah (i)
pelaku usaha, (ii) membuat perjanjian, (iii) pelaku
usaha pesaing, (iv) yang bertujuan untuk mempengaruhi
harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran,
(v) suatu barang dan/atau jasa, (vi) yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau
persaingan usaha tidak sehat.
a. Pelaku Usaha
Definisi pelaku usaha dijabarkan dalam pasal 1 ayat
5 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut:
“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum atau badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan
usaha dalam bidang ekonomi.”
Universitas Indonesia
61
b. Perjanjian
Pengertian ’Perjanjian’ dalam UU No. 5 Tahun 1999
diatur dalam pasal 1 ayat (7) UU No. 5 Tahun 1999
sebagai berikut:
“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau
lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri
terhadap satu atau lebih usaha lain dengan
nama apapun, baik tertulis maupun tidak
tertulis.”
c. Pelaku Usaha Pesaingnya
Elemen Pelaku Usaha Pesaingnya terkait erat dengan
pasar bersangkutan yang dijelaskan lebih lanjut
dalam pedoman pelaksana pasal 1 ayat 10 tentang
Pasar Bersangkutan yang diberikan oleh KPPU melalui
Surat Keputusan No. 3 Tahun 2009.92
d. Bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara
mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang
dan/atau jasa
Unsur ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) sub-
unsur, yaitu tujuan dan cara. Tujuan akhir dari
perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku pesaing
adalah pada untuk mempengaruhi harga. Caranya adalah
dengan mengatur produksi dan/atau pemasarang suatu
barang dan/atau jasa. Dengan kata lain, perjanjian
92 KPPU, Keputusan KPPU No. 3 tahun 2009 tentang PedomanPelaksana Pasal 1 ayat 10 UU No. 5 Tahun 1999 tentang PasarBersangkutan, hal. 17.
Universitas Indonesia
62
dengan metode penetapan harga tidak terjerat pasal
11, melainkan pasal 5. Perbedaan utama pasal 11 dan
5 adalah pada pasal 11 unsur “mempengaruhi harga”
adalah tujuan akhir, sementara pada pasal 5 unsur
“menetapkan harga” adalah cara/metodenya.
Pasal 1 ayat 8 memberikan definisi mengenai
Persekongkolan sebagai berikut:
“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk
kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan
pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai
pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha
yang bersekongkol.”
Pasal 1 ayat 9 mengenai definisi Pasar:
“Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para
pembeli dan penjual baik secara langsung
maupun tidak langsung dapat melakukan
transaksi perdagangan barang dan atau jasa.”
Pasal 1 ayat 10 mengenai definisi Pasar Bersangkutan
“Pasar Bersangkutan adalah pasar yang
berkaitan dengan jangkauan atau daerah
pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas
barang dan atau jasa yang sama atau sejenis
atau substitusi dari barang dan atau jasa
tersebut.”
Universitas Indonesia
63
Pasal 1 angka 16 mendefinisikan Barang sebagai
berikut:
“Barang adalah setiap benda, baik berwujud
maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun
tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan
oleh konsumen atau pelaku usaha.”
Pasal 1 angka 17 mendefinisikan Jasa sebagai
berikut:
“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk
pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan
dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh
konsumen atau pelaku usaha.”
e. ”yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat”
Pasal 1 ayat 2 mengenai definisi praktek
monopoli menyatakan:
“Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan
ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang
mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau
pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu
sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak
sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”
Universitas Indonesia
64
Pasal 1 ayat 6 mengenai definisi persaingan
usaha tidak sehat:
“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan
antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum
atau menghambat persaingan usaha.”
3.3 Ciri-ciri kartel
Ciri-ciri kartel adalah sebagai berikut.93
a. Kartel bersifat rahasia dan dan sangat sulit untuk
dideteksi. Oleh karena itu, kartel sulit dideteksi
oleh otoritas, apalagi konsumen.
b. Kartel hanya menguntungkan pelaku atau anggotanya
dan tidak mempunyai dampak positif bagi konsumen
melalui mekanisme yang lebih efisien
c. Kartel mempunyai dampak yang sangat buruk bagi
persaingan. Kriminalisasi kartel akan meningkatkan
efek jera serta efektifitas larangan kartel.
3.4. Bentuk kartel
Terkait dengan bentuk kartel, OECD mendefinisikan
hard-core cartel sebagai “perjanjian anti-kompetisi,
praktek anti-kompetitif yang concerted atau pengaturan
93 Manatu Ohanga, op.cit., hal. 17.
Universitas Indonesia
65
anti-kompetisi oleh para pelaku usaha yang bersaing
untuk:94
a. Menetapkan harga,
b. Tender kolusif (bid-rigging)
c. Membatasi output atau melakukan kuota, atau
d. Membagi atau memisahkan pasar dengan
mengalokasikan konsumen, pemasok, wilayah,
atau batas komersial.
Selain 4 (empat) bentuk hard-core cartel seperti yang
telah dijelaskan di atas, juga terdapat kartel dalam
bentuk lain yang belum jelas harus dikriminalisasi atau
tidak. Keempat bentuk kartel tersebut adalah:95
a. Kartelis dengan pangsa pasar kecil (the minor
cartelist)
b. Kartelis yang tidak kompeten/mampu (the
incompetent cartelist)
c. Kartelis yang tidak beruntung (the unlucky
cartelist)
d. Kartelis yang naif/bodoh (the naïve cartelist)
1. The minor cartelist
The minor cartelist adalah kartelis yang mempunyai
maksud dan tujuan untuk membentuk kartel, namun dampak
buruk yang disebabkannya kecil karena sifat dan cakupan
kegiatan usahanya yang kecil. Bayangkan ada 2 (dua)94 OECD Recommendation of the Council Concerning Effective Action Against Hard
Core Cartels (diadopsi oleh Dewan pada rapat sesi 921 pada tanggal 25Maret 1998 [C/M (98) 7/PROV]).
95 Manatu Ohanga, op.cit., hal. 36.
Universitas Indonesia
66
produsen susu yang sepakat untuk menetapkan harga.
Asumsikan pula pasar mereka dibatasi oleh kondisi
geografis karena konsumen produk mereka merasa malas
untuk menempuh perjalanan yang jauh untuk membeli
produk mereka. Kedua produsen sepakat untuk menetapkan
harga untuk 10 jenis susu. Kartel ini mungkin saja
sukses, namun dampak ekonominya sangat kecil karena
pendapatan kotor mereka hanya sebesar USD 100.000 per
tahun.
Apakah kartel yang dampaknya terhadap ekonomi
begitu kecil harus dikriminalisasi? Pada umumnya,
pendekatan yang diterapkan adalah dengan tetap
mengkriminalisasi kartel, namun jaksa penuntut umum
diberikan diskresi untuk tidak menuntut kartel yang
berdampak kecil terhadap ekonomi. Pedoman Penuntutan
Australia (Australian Prosecution Guidelines) menyatakan lebih
kecil kemungkinan adanya penuntutan terhadap pelaku
kartel atas kartel yang mempunyai dampak ekonomi kurang
dari AU$ 1 juta jika tidak ada faktor pemberat lainnya.
Jika legislator menggunakan batas peraturan perundang-
undangan (statutory threshold) daripada pedoman penuntutan,
maka calon pelaku kartel akan lebih terdorong untuk
melakukan kartel dengan mengeksploitasi marjin AU$ 1
juta tersebut. Caranya adalah dengan mendiversifikasi
produknya dan menetapkan kerugian kartel sebesar AU$
999.999 per satu jenis produknya.
Universitas Indonesia
67
2. The incompetent cartelist
The incompetent cartelist adalah kartelis yang mengadakan
perjanjian kartel dengan maksud dan tujuan untuk
mengurangi persaingan di antara pihak-pihak yang
terlibat dalam perjanjian tersebut. Kartel tidak
berhasil karena para kartelis tersebut tidak kompeten
untuk membuat kartel yang baik. Para kartelis ini hanya
memiliki 35% pangsa pasar sehingga ketika para kartelis
menaikkan harga produk dan pelaku usaha pesaing para
kartelis ini mengurangi harga produknya, mereka
kehilangan pangsa pasar dan keuntungan yang mereka
harapkan.
Sistem hukum Anglo-Saxon mengenal pembelaan atas
ketidakmungkinan melakukan konspirasi (a defence of
impossibility for conspiracy). Contohnya, dalam kasus DPP v
Nock di Inggris,96 seorang terdakwa dibebaskan walaupun
dia sudah setuju untuk memproduksi morfin melalui zat-
zat kimia tertentu, karena hal tersebut tidak
dimungkinkan berdasarkan disiplin ilmu kimia.
Prinsip ini tidak diikuti oleh Selandia Baru dalam
kasus R v. Sew Hoy karena situasi di atas mirip dengan
percobaan (poging) melakukan kejahatan.97 Pembentukkan
kartel adalah bertentangan dengan kepentingan publik
(public interest) dan incompetent cartelist bisa saja berhasil
96 Director of Public Prosecutions v. Nock and Another, Houseof Lords AC 979 (1978) dikutip dari Ibid hal. 37
97 Manatu Ohanga, op.cit., hal. 37.
Universitas Indonesia
68
membentuk kartel dalam percobaan berikutnya. Oleh
karena itu, incompetent cartelist juga dikriminalisasi
menurut RIA tentang kriminalisasi kartel Selandia
Baru.98
3. The unlucky cartelist
The unlucky cartelist mengadakan perjanjian kartel, namun
karena kondisi dan situasi di luar controlnya,
perjanjian kartel tersebut tidak bisa
dilaksanakan/diimplementasikan. Contohnya, perubahan
kondisi pasar akibat perubahan kurs dolar Amerika
Serikat terhadap rupiah Indonesia sehingga harga produk
para kartelis naik 100%. Karena bahan baku diimpor,
harga produk para kartelis naik 100% sehingga penetapan
harga tinggi menjadi tidak berguna.
4. The naïve cartelist
The naïve cartelist membentuk kartel tanpa menyadari
bahwa kartel itu illegal. Kartelis ini bahkan mungkin
memberitahukan pihak lain bahwa mereka mengadakan
perjanjian penetapan harga. Hal ini lumrah terjadi.
Beberapa pelaku usaha malah menganggap persaingan harga
merupakan pelanggaran terhadap etika bisnis. Tanggung
jawab the naïve cartelist tergantung pada apakah unsur
tujuan (intention) relevan. Britania Raya mempersyaratkan
unsur ketidakjujuran untuk kejahatan kartel agar the
98 Ibid.
Universitas Indonesia
69
naïve cartelist bisa lolos dari tanggung jawab berdasarkan
ketidaktahuan atau ketidakmungkinan untuk mengetahui
secara wajar (reasonably know or should have known) dengan
standar orang awam (ordinary people).99 Sebaliknya, hukum
persaingan usaha di Australia dan Kanada tetap menuntut
pertanggungjawaban the naïve cartelist.100
3.5. Dasar Kriminalisasi Kartel
3.4.1Terkait makna (arti) kejahatan: kartel
merupakan suatu kejahatan
Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab I bahwa
terdapat perbedaan antara pendekatan faktual dengan
normatif. Teori faktual menyatakan bahwa suatu
perbuatan merupakan kejahatan karena ada hukum positif
(formal) yang mengkriminalisasinya. Pendekatan ini
adalah ciri utama dari paham formalisme yang menyatakan
bahwa kejahatan adalah produk dari reaksi sosial.
Sementara, teori normatif menyatakan suatu perbuatan
merupakan kejahatan karena sifat (nature) dari perbuatan
tersebut, bukan karena ada hukum positif (formal) yang
engkriminalisasinya semata. Pada bagian ini, Penulis
akan mengkaji dasar kriminalisasi kartel berdasarkan
pendekatan teori normatif dan teori-teori lanjutannya.
99 Ibid.
100 Ibid.
Universitas Indonesia
70
3.4.1.1 Berdasarkan pendekatan teori
normatif
Dua unsur utama kejahatan, yang secara umum
dirumuskan, dalam pendekatan teori normatif (seperti
yang telah dijelaskan di Bab II) adalah (i) harm dan
(ii) damage. Definisi harm dalam Black’s Law Dictionary
adalah “injury, loss; material or tangible detriment”101. Harm
dibagi menjadi accidental harm,102 bodily harm,103 physical
harm,104 dan social harm105. Sementara definisi damage
dalam adalah “loss or injury to person or property”106 Kata
damage-cleer dalam bahasa Latin adalah damma clericorum
atau dalam bahasa Inggris clerk’s compensation. Damage
merupakan biaya yang ditentukan untuk dibayarkan oleh
penggugat dalam the Court of the Common Please King’s Bench di
Inggris atau biaya yang harus dibayarkan sebelum
putusan ganti rugi dijatuhkan oleh hakim.107 Dengan
101 Garner, op.cit., hal 734.
102 Ibid. Harm yang tidak disebabkan oleh perbuatan melawanhukum (tortious act)
103 Ibid. Rasa sakit secara fisik, kesakitan atau penyakit,atau kerusakan tubuh.
104 Ibid. Kerusakan fisik terhadap tanah, benda atau properti,dan tubuh manusia.
105 Ibid. Dampak buruk terhadap kepentingan umum/sosial yangdilindungi oleh hukum pidana. Semua kejahatan meliputi (i)terjadinya social harm, dan (ii) fakta bahwa perbuatan orangtertentu adalah sebab dari harm tersebut.
106 Ibid, hal 416.
107 Ibid.
Universitas Indonesia
71
demikian, dapat disimpulkan bahwa harm juga meliputi
kerugian dalam konteks rasa sakit terhadap fisik dan
psikis manusia, nilai moral, norma sosial, dan benda
atau properti. Sementara damage lebih berorientasi pada
kerusakan yang senyatanya diderita oleh subyek hukum
(orang atau badan hukum) sehingga bisa dikuantifikasi
dalam bentuk uang untuk dimintakan ganti rugi (monetary
compensation).
Secara umum, kartel menyebabkan harm dan damage
karena alasan sebagai berikut.
1. Kartel merupakan perbuatan yang mempunyai asosiasi
sangat erat dengan pencurian dan/atau penipuan.
Pencurian dan/atau penipuan tidak hanya
menyebabkan kerugian uang (monetary compensation),
namun juga menyebabkan kerugian moral (social harm)
dan kerugian fisik serta moral terhadap benda
(physical harm).
2. Gorofalo (yang berorientasi pada pendekatan teori
normatif) mempostulasikan teori “kejahatan
natural” (natural crime) yang meliputi pembunuhan,
pemerkosaan, pencurian, dan pembakaran benda atau
properti. Oleh karena pencurian merupakan
kejahatan natural, maka secara analogis dan
asosiatif kartel juga merupakan kejahatan natural.
3. Kartel mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya
secara tidak adil dari pihak berkuatan ekonomi
jauh lebih kuat dari pihak yang berkuatan ekonomi
Universitas Indonesia
72
jauh lebih lemah. Terhadap kejahatan yang
demikian, pasal 166, 167, dan 168 KUHP Republik
Demokrasi Jerman mengancam pidana.108 Unsur yang
paling fundamental dari sifat jahat kartel adalah
struktur yang memungkinkan terjadinya kartel yaitu
struktur dimana masyarakat yang berkekuatan
ekonomi lebih lemah menghadapi segelintir
pengusaha dengan kekuatan ekonomi yang jauh lebih
kuat. Dalam pencurian, pencuri pada umumnya adalah
masyarakat berekonomi lemah yang berhadapan dengan
masyarakat yang berekonomi kuat atau setidaknya
pencuri dengan korban berada dalam kekuatan
ekonomi yang sama. Memang pencurian juga mungkin
terjadi dalam konteks pencurinya adalah masyarakat
berekonomi relatif lebih kuat dan korbannya adalah
masyarakat berekonomi relatif lebih lemah. Namun,
perbedaan utama pencurian dengan kartel adalah
kartel lahir dalam konteks “pencurinya” adalah
masyarakat berkekuatan ekonomi sangat kuat,
sementara korbannya berkekuatan ekonomi jauh lebih
lemah dibandingkan “pencurinya”. Oleh karena itu,
kartel sering disebut juga sebagai white collar
crime.109
108 A. Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi, Edisi Revisi, (Jakarta:Erlangga,1996), hal 9.
109 Barda Nawawi Arief, op.cit., hal 13. Sifat kartel adalahsulit dideteksi, terorganisasi dengan baik, dilakukan oleh merekayang punya kedudukan terpandang dalam masyarakat, merugikankonsumen, dan yang lebih sulit lagi adalah untuk diatasi.
Universitas Indonesia
73
4. Selain disparitas kekuatan ekonomi, kartel juga
merenggut kebebasan memilih atau kebebasan ekonomi
seorang konsumen. Jika dalam pencurian konsumen
yang dicuri uangnya masih akan menyadari
kehilangan uangnya, maka dalam kartel konsumen
umumnya tidak mengetahui/menyadari “dicurinya”
uang tersebut. Pencurian dalam kartel dilakukan
dengan “topeng” mekanisme harga dalam pasar,
sehingga konsumen umumnya tidak mengetahui atau
menyadari bahwa uang mereka dicuri melalui
penetapan harga dan kontrol produksi atau
pemasaran. Selain itu, kartel juga bertujuan untuk
mematikan atau menghambat pelaku usaha pesaing
yang aktual maupun potensial sehingga produk pasar
terkonsentrasi pada pelaku kartel. Akibatnya,
insentif menurunkan harga barang dan/atau jasa,
menaikkan kualitas barang dan/atau jasa, serta
inovasi dan diversifikasi menjadi berkurang atau
hilang. Akibat kartel tersebut merupakan
perenggutan terhadap kebebasan konsumen atas
kebebasannya memilih. Jadi dampak kartel bersifat
aktual maupun potensial terhadap baik konsumen
maupun pelaku usaha.
3.4.1.2 Berdasarkan pendekatan konsekuensi
perbuatan
Universitas Indonesia
74
Teori konsekuensi perbuatan yang dipostulasikan
Michael J. Allen pada dasarnya menyatakan bahwa“ketika
pembentuk undang-undang menentukan bahwa perbuatan
tertentu adalah kejahatan, sifat (nature) dari perbuatan
tersebut tidak berubah, namun konsekuensi dari
melakukan perbuatan tersebut yang berubah.” Dengan kata
lain, terdapat perbuatan yang sudah dinilai salah atau
jahat. Namun, pengkriminalisasian perbuatan tersebut
tidak mengubah sifat (nature) salah atau jahat dari
perbuatan tersebut, melainkan hanya memperberat
konsekuensi dari perbuatan yang dinilai salah atau
jahat tersebut. Pemberatan konsekuensi dari perbuatan
tersebut disebabkan tidak efektif dan efisiennya
sanksi-sanksi lain di luar sanksi pidana. Pendekatan
ini bersifat lebih pragmatis (mirip dengan pendekatan
faktual) dibandingkan dengan pendekatan normatif. Dalam
spektrum waktu, pendekatan konsekuensi perbuatan
merupakan langkah selanjutnya dari pendekatan normatif.
Kartel (hard-core cartel) merupakan perbuatan yang
secara faktual sudah dinilai salah atau jahat, namun
dalam sejarah hukum persaingan usaha, contohnya,
Amerika Serikat, kartel hanya dihukum dengan sanksi
administrasi dan/atau ganti rugi perdata. Ketika
Amerika Serikat mengkriminalisasi perbuatan kartel,
sifat (nature) dari perbuatan kartel yang salah atau
jahat tidak berubah, melainkan konsekuensi dari
perbuatan tersebut yang berubah. Konsekuensi yang
Universitas Indonesia
75
dimaksud adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana
denda. Dengan kata lain, konsekuensi atas perbuatan
kartel diperberat.
Terkait pendekatan konsekuensi perbuatan, kartel
merupakan kejahatan yang pantas mendapatkan hukuman
yang berat karena mempunyai harm dan damage yang besar
terhadap konsumen, pelaku usaha, dan kesejahteraan
umum.
3.4.1.3 Berdasarkan kriteria-kriteria untuk
menentukan suatu perbuatan suatu
kejahatan
Herbert Packer menjabarkan beberapa kriteria untuk
menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan,
diantaranya, sebagai berikut.
1. Mayoritas masyarakat tersebut memandang perbuatan
tersebut sebagai ancaman sosial.
2. Perbuatan tersebut tidak pernah
ditoleransi/diizinkan oleh sebagian besar kalangan
masyarakat.
3. Menekan/mengisolasi perbuatan tersebut tidak akan
menghalangi perbuatan yang diinginkan masyarakat
luas (socially desirable conduct).
4. Tidak ada alternatif lain yang masuk akal selain
sanksi pidana untuk mengatasi masalah tersebut.
Kartel termasuk kejahatan (tindak pidana) karena:
Universitas Indonesia
76
1. Mayoritas masyarakat memandang kartel sebagai
ancaman sosial. Pertama, kartel secara analogis
dan asosiatif mirip dengan pencurian. Masyarakat
memandang pencurian sebagai ancaman sosial. Hal
ini terbukti dengan dikriminalisasinya perbuatan
pencurian di rezim hukum pidana hampir semua
negara di dunia. Kedua, kartel mempunyai dampak
yang bahkan lebih buruk daripada sekedar pencurian
karena kartel menyebabkan kerugian nyata (aktual)
dan potensial terhadap konsumen, pelaku usaha, dan
kesejahteraan umum. Ketiga, kartel dilakukan
dengan metode yang sangat canggih (advanced) dan
sangat susah dideteksi apalagi ditangkap dan
dibuktikan di pengadilan.
2. Jika perbuatan mencuri tidak pernah ditoleransi
masyarakat, maka perbuatan kartel juga tidak
ditoleransi masyarakat.
3. Menekan/mengisolasi kartel tidak akan menghalangi
perbuatan yang diinginkan masyarakat luas, yaitu
kebebasan memilih atau kebebasan ekonomi serta hak
ekonomi atas harga barang dan/atau jasa yang lebih
murah.
4. Tidak ada alternatif lain yang masuk akal selain
sanksi pidana untuk mengatasi/menangani kartel.
Kartel dilakukan dengan metode yang sangat canggih
(advanced) dan sangat susah dideteksi apalagi
ditangkap dan dibuktikan di pengadilan. Oleh
Universitas Indonesia
77
karena itu, negara harus turun tangan untuk
melabel kartel sebagai suatu kejahatan sehingga
tingkat perhatian dan keseriusan terhadap
penanganan kartel menjadi tinggi. Di Amerika
Serikat, penentuan kartel sebagai kejahatan
menjadi legitimasi pembentukan otoritas persaingan
usaha dengan sumber daya manusia, infrastruktur,
dan pendanaan yang besar.110 Pelabelan kartel
sebagai kejahatan meningkatkan rasa mawas diri
dari pelaku kartel karena (i) label “kejahatan”
merusak nama baik korporasi besar, dan (ii) sanksi
atas kartel diperberat.
3.4.2Terkait tujuan hukum pidana
Tujuan hukum pidana (seperti yang telah dijelaskan
dalam Bab II) diantaranya adalah adalah pembalasan,
prevensi umum, prevensi khusus, menegakkan hukum,
menyelesaikan konflik-konflik, membatasi dan
menghindarkan “main hakim sendiri”.
Terkait dengan tujuan hukum pidana, kriminalisasi
kartel bertujuan untuk:
1. Mendera atau membalas para pelaku kartel atas
harm dan damage yang sudah ditimbulkan.
2. Mencegah (preventif) terjadinya kartel di masa
yang akan datang.
110 Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Bab IV Skripsi ini.
Universitas Indonesia
78
3. Menciptakan stigma terhadap kartel karena dampak
buruk yang ditimbulkan kartel, kesulitan
mendeteksi dan menangkap pelaku kartel,
meningkatkan rasa mawas diri dari pelaku kartel,
dan memperberat sanksi atas kartel.
4. Menyelesaikan kepentingan yang berbeda-beda. Di
satu sisi, pelaku kartel yang mengejar keuntungan
sebesar-besarnya dengan metode yang canggih
(advanced) dan mengorbankan kepentingan konsumen,
pelaku usaha lain, dan kesejahteraan umum. Di
sisi lain, konsumen mempunyai hak kebebasan
ekonomi dan kebebasan memilih sementara pelaku
usaha lain mempunyai hak atas kesempatan
berusaha (aktivitas ekonomi), berinovasi, dan
memperoleh penghidupan yang layak atau
kesejahteraan.
5. Menciptakan takaran atau timbangan bahwa
kepentingan konsumen dan pelaku usaha tersebut
berada di atas kepentingan segelintir pelaku
kartel. Dengan demikian, kartel merupakan suatu
social deviant behaviour dimana pelakunya pantas
disebut sebagai penjahat dan dikenai hukuman yang
paling berat, yaitu sanksi pidana.
3.4.3Terkait fungsi hukum pidana
Fungsi hukum pidana (seperti yang telah dijelaskan
dalam Bab II Skripsi ini) diantaranya adalah (i)
Universitas Indonesia
79
retribusi (ii) pelumpuhan, dan (iii) deteren. Terkait
dengan fungsi hukum pidana, pengkriminalisasian kartel
berfungsi untuk:
1. Menciptakan kepastian dan pembenaran bagi korban
kejahatan atas rasa benci mereka atas kejahatan
kartel yang dilakukan. Dengan dikriminalisasinya
kartel, maka terdapat pembenaran (justification) bagi
korban kejahatan untuk menyatakan perbuatan kartel
immoral dan/atau patut dijatuhkan hukuman yang
berat. Selain itu, fungsi kriminalisasi kartel
adalah juga untuk membenarkan kecaman publik
(denunciation) atas kejahatan kartel. Dengan
dikriminalisasinya kartel, publik bisa menunjukkan
ketidaksetujuannya atas kejahatan tersebut dan
mendapatkan alasan yang cukup atas
ketidaksetujuannya.
2. Sanksi pidana mampu menciptakan efek jera yang
lebih besar dibandingkan sanksi lainnya. Pelaku
kartel pada umumnya adalah individu dalam
korporasi besar yang dalam kenyataan sehari-
harinya dipandang sebagai masyarakat yang taat
hukum. Sanksi pidana merupakan sanksi yang paling
berat dan memalukan bagi orang-orang dalam kelas
tersebut. Oleh karena itu, kriminalisasi kartel
mampu menciptakan efek jera yang besar bagi pelaku
kartel.
Universitas Indonesia
80
3. Berhubung pelaku kartel merupakan makhluk ekonomi
yang mementingkan keuntungan sekaligus individu
yang hakiki, maka sanksi pidana penjara dan denda
sekaligus mampu melumpuhkan aktivitas kartel.
Sanksi pidana denda yang relatif besar mampu
menciptakan efek jera karena pelaku kartel
bertumpu pada keunggulan ekonominya dalam
menjalankan/melakukan kartel. Sanksi pidana
penjara mampu menciptakan kecaman publik sehingga
pelaku maupun calon pelaku kartel, yang pada
umumnya mereka anggota masyarakat yang dianggap
taat hukum, akan berpikir berkali-kali sebelum
mereka menjalankan/melakukan kartel. Selain itu,
korporasi besar juga bertumpu pada nama baik dalam
menjalankan kegiatan usahanya. Label kriminal akan
secara sistematis menghancurkan kredibilitas suatu
korporasi besar yang sudah dibangun dengan susah
payah dalam kurun waktu yang lama. Dengan sanksi
pidana penjara, pelaku kartel akan menghadapi
resiko yang lebih besar daripada keuntungan yang
didapatkannya sehingga pelaku maupun calon pelaku
kartel mempunyai insentif yang besar untuk
mematuhi hukum (tidak melakukan kartel).
3.4.4Dampak buruk kartel
Universitas Indonesia
81
3.4.4.1 Kartel secara analogis dan asosiatif
merupakan pencurian
Dampak buruk kartel seperti yang dijelaskan pada
paragraf sebelumnya, merupakan alasan utama kartel
dikriminalisasi. Dalam bab ini akan diuraikan secara
lebih rinci kaitan dampak buruk tersebut dengan
kriminalisasi kartel serta pemaparan kesamaan/kemiripan
kartel dengan pencurian. Dengan kata lain, kartel
merupakan bentuk perbuatan mencuri. Berikut adalah
uraian elemen pencurian.
Secara umum, pencurian dikriminalisasi karena
perbuatan tersebut mengambil hak milik orang lain yang
tidak diperolehnya sendiri. Dalam pendekatan
utilitarianisme, orang seperti itu harus diberikan
sanksi pidana bentuk penjara supaya pencuri tersebut
tidak melakukan perbuatan menyakiti (harm) dan merusak
(damage) kepada orang lain. Dalam pendekatan
retributif, pencuri tersebut harus dipenjara karena
dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari norma sosial
yang umum (deviant social behaviours) supaya tidak mengganggu
ketenangan masyarakat. Selain itu pendekatan retributif
juga melihat bahwa tindakan pencurian harus
dikriminalisasi untuk memberikan rasa
adil/tenang/terpuaskan dari anggota masyarakat yang
merasa haknya diambil secara paksa dan melawan
keinginannya. Dalam pendekatan rehabilitatif, pencuri
tersebut perlu dididik secara disiplin di penjara untuk
Universitas Indonesia
82
(i) memahami secara jelas konsekuensi dari tindakan
mencuri dan (i) memahami bahwa tindakan tersebut
menimbulkan rasa jijik (disgust) (dalam bahasa Lord Devlin)
dan bahwa masyarakat memandang itu sangat ditentang dan
dibenci oleh masyarakat. Didikan dengan penjara
tersebut dipandang mampu dan perlu untuk mengubah pola
perilaku pencuri yang bertentangan dengan norma
masyarakat umum, sehingga pada akhirnya pencuri
tersebut bisa dikembalikan ke masyarakat untuk
berfungsi secara normal berdasarkan norma-norma umum
yang diterima masyarakat.
Jika kita mengaplikasikan pendapat D. Simons yang
menekankan pada fungsi hukum pidana sebagai pelindung
kepentingan individu yang juga merupakan kepentingan
bagi masyarakat luas, maka, pencurian dikriminalisasi
kepentingan individu dan masyarakat luas yang terancam.
Kepentingan tersebut dianggap patut dilindungi dengan
memenjarakan pencuri karena keinginan atas rasa aman
yang dituntut oleh setiap individu maupun masyarakat.
Pencurian bukan hanya merupakan sekedar perbuatan yang
menghilangkan/mengambil suatu barang sehingga bisa
selesai (terestitusi) dengan pengembalian barang atau
sejumlah uang sebesar nilai barang tersebut. Pencurian
juga menyebabkan hilangnya rasa aman dan kepercayaan
terhadap sesama individu dalam tatanan sosial, sehingga
penjara (sanksi pidana) diperlukan untuk membedakan
Universitas Indonesia
83
sorang pencuri dan seorang individu yang bukan
merupakan pencuri.
Dalam tataran yang lebih pragmatis, Ashworth
menggariskan dua indikator mengapa suatu perbuatan
harus dikriminalisasi yaitu (i) apakah perbuatan
tersebut mempunyai dampak buruk berupa rasa sakit
(harmful) kepada individu atau masyarakat? dan (ii)
apakah perbuatan tersebut amoral?111 Jika kita
mengaplikasikan indikator Ashworth, maka pencurian
merupakan perbuatan yang dikriminalisasi karena
mempunyai dampak buruk (harmful) kepada individu atau
masyarakat dan bersifat amoral.
Dalam pendekatan yang positivistik berdasarkan
Pasal 362 KUHP, pencurian dinyatakan sebagai berikut.
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena
pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun
atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”
Unsur-unsur pasal 362 KUHP yang penting dan terkait
dengan pembahasan Skripsi ini adalah (i) mengambil
barang, (ii) kepunyaan orang lain, (iii) dengan maksud
untuk dimiliki, dan (iv) secara melawan hukum.
111 A. Ashworth, op.cit.
Universitas Indonesia
84
Pasal lain yang terkait dengan kartel adalah Pasal
382bis KUHP tentang perbuatan curang yang menyatakan:
“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan
atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan
milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan
curang untuk menyesatkan khalayak umum atau
seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu
dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-
konkurennya atau konguren-konkuren orang lain,
karena persaingan curang, dengan pidana penjara
paling lama satu tahun empat bulan atau pidana
denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus
rupiah.”
Unsur-unsur pasal 382bis yang penting dan terkait
dengan pembahasan Skripsi ini adalah (i) melakukan
perbuatan curang, (ii) untuk menyesatkan khalayak umum
atau seorang tertentu, untuk (iv) mendapatkan,
melangsungkan, atau memperluas, dan (v) hasil
perdagangan atau perusahan milik sendiri atau orang
lain.
3.4.4.2 Pengalihan surplus konsumen kepada
produsen merupakan pencurian sehingga
perbuatan pengalihan tersebut
dikriminalisasi
Universitas Indonesia
85
Sebagai pengantar bagian ini, Penulis mengutip
pernyataan Anne K. Bingman dalam pidato pembukaan di
Departement of Justice Amerika Serikat.112 Beliau menyatakan
bahwa “pelaku yang melakukan tender kolusif (salah satu
bentuk kartel), membagi pasar atau menetapkan harga
mengambil uang dari kantong konsumen Amerika Serikat
dan mencuri uang dari ‘mesin kasir’ bisnis Amerika, dan
ini sama saja dengan merampok sebuah rumah di malam
hari dengan masuk secara diam-diam dalam kegelapan.”
Pelaku kartel adalah kriminal karena mereka
menaikan harga, menurunkan kualitas dan membatasi
pilihan konsumen. Dalam perspektif yang sempit, mereka
mencuri uang dari konsumen. Dalam perspektif yang lebih
luas, pelaku kejahatan tersebut menghancurkan sendi-
sendi hidup masyarakat. Suatu masyarakat yang
menoleransi kejahatan kartel tidak bisa melindungi
kebebasan ekonominya, sama halnya dengan masyarakat
yang menoleransi pembunuhan tidak bisa melindungi
kebebasan fisiknya.113 Terkait dengan pentingnya
perlindungan masyarakat dari dampak buruk kartel,
Senator John Sherman menyatakan “Saya tidak mengetahui
112 Anne K.Bingman dan Gary R. Spratling, Criminal AntitrustEnforcement, dalam Criminal Antitrust Law and Procedure WorkshopABA Section ofAntitrust, Hyatt Regency Hotel Dallas, Texas, February 23, 1995.Lihat di http://www.justice.gov/atr/public/speeches/0103.pdf(kunjungan terakhir 25 Mei 2010).
113 Ibid.
Universitas Indonesia
86
obyek apa lagi yang lebih penting dari perlindungan hak
tersebut.”114
Selanjutnya, kartel memenuhi unsur-unsur Pasal 362
dan 382bis KUHP. Pertama, unsur-unsur pasal 362 KUHP
adalah (i) mengambil barang, (ii) kepunyaan orang lain,
(iii) dengan maksud untuk dimiliki, dan (iv) secara
melawan hukum. Pengalihan surplus konsumen ke produsen
dalam bentuk marjin harga sama dengan mengambil barang
yang bukan kepunyaannya dengan maksud untuk dimiliki
oleh produsen dan perbuatan ini dilakukan secara
melawan hukum. Perbuatan melawan hukum muncul ketika
pengambilan barang tersebut (i) tidak dengan
persetujuan dari konsumen atau (ii) dilakukan dengan
menipu konsumen sehingga seolah-olah konsumen
menyetujui harga produk yang ditawarkan di pasar,
padahal konsumen ditipu oleh produsen dengan
menghilangkan produk yang seharusnya lebih efisien dan
oleh karenanya lebih murah. Konsumen dipaksa untuk
membayarkan sejumlah uang yang tidak seharusnya ia
bayarkan kepada produsen untuk barang yang sama pada
waktu dan ruang yang sama dan ini sama saja dengan
mengambil uang dari kantong konsumen.
Kedua, unsur-unsur penting dan terkait dengan
pembahasan Skripsi ini adalah (i) melakukan perbuatan
curang, (ii) untuk menyesatkan khalayak umum atau
seorang tertentu, untuk (iv) mendapatkan,
114 Ibid.
Universitas Indonesia
87
melangsungkan, atau memperluas, dan (v) hasil
perdagangan atau perusahan milik sendiri atau orang
lain. Kartel adalah perbuatan curang karena dilakukan
dengan menipu konsumen sehingga seolah-olah konsumen
menyetujui harga produk yang ditawarkan di pasar,
padahal konsumen ditipu oleh produsen dengan cara
menghilangkan produk yang seharusnya lebih efisien dan
oleh karenanya lebih murah dari pasar. Dengan kata
lain, konsumen dipaksa untuk membayarkan sejumlah uang
yang tidak seharusnya ia bayarkan kepada produsen untuk
barang yang sama pada waktu dan ruang yang sama.
Perbuatan di atas juga merupakan penyesatan khalayak
umum terhadap persepsi konsumen atas harga yang barang
yang seharusnya atau pantas dan dilakukan untuk
mendapatkan keuntungan maksimum untuk perusahaan milik
sendiri ataupun orang lain.
Alasan paling fundamental dikriminalisasinya kartel
adalah kebebasan konsumen yang direnggut seluruhnya.
Pertama, konsumen tidak memiliki pijakan yang berimbang
(equal footing) dengan korporasi raksasa dalam hal
informasi dan hal ini menyebabkan information asymmetry.115
Akibatnya, korporasi raksasa bisa mengeksploitasi
kondisi tersebut dengan menetapkan harga (price setter).
Hukum persaingan usaha berfungsi melindungi kaum
115 Information asymmetry terjadi akibat salah satu pihak dalamtransaksi mempunyai informasi yang lebih banyak atau lebih baikdari pihak lainnya. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalamtransaksi dimana satu pihak bisa mengeksploitasi ketidaktahuanatau ketidaktersediaan informasi kepada pihak lain.
Universitas Indonesia
88
konsumen yang lebih ‘lemah’ dari kewenangan korporasi
raksasa dengan cara mendistribusi kekuasaan price setter
kepada beberapa pelaku usaha untuk memastikan
keberadaan kompetisi yang sehat di antara pelaku usaha.
Seperti halnya dua kutub yang berlawanan dan saling
tarik menaruk, tujuan kartel berada pada kutub yang
berseberangan dengan tujuan hukum persaingan usaha.
Kartel berusaha menarik pasar ke arah kekuasaan price
setter yang lebih besar sementara hukum persaingan usaha
menarik ‘pegas’ pasar ke arah kekuasaan price setter yang
lebih rendah.
Kedua, akibat dari tidak adanya equal footing
tersebut, konsumen kehilangan kebebasan ekonomi atau
lebih tepatnya tidak mengetahui bahwa kebebasan
ekonominya telah direnggut. Bayangkan seorang konsumen
dan asumsikan harga beras pada umumnya adalah Rp.
5.000/kg. Jika hari ini semua beras yang tersedia di
pasar (dalam hal kuantitas maupun kualitas) dijual
dengan harga minimum Rp. 8.000/kg, maka konsumen
terpaksa harus membelinya juga. Kebebasan ekonomi
konsumen atas beras seharga Rp. 5.000/kg direnggut
karena tidak adanya pilihan lain. Selain itu,
dikarenakan struktur ‘makhluk hidup’ yang memerlukan
makanan dan nasi bersifat inelastis di Indonesia,
konsumen harus membayar Rp. 8.000/kg beras. Lebih buruk
lagi, konsumen bahkan tidak mengetahui bahwa ia
membayar lebih mahal daripada yang anda seharusnya
Universitas Indonesia
89
bayar, karena konsumen hanya akan menerima bahwa
mungkin Rp. 8.000/kg beras adalah harga pasar. Hampir
tidak mungkin dibayangkan seorang konsumen mempunyai
sumber daya (resources) yang cukup untuk melakukan
penelitian yang membuktikan tingkat harga pasar
seharusnya adalah Rp. 5.000/ kg beras dan pelaku usaha
beras menaikkan harganya menjadi sebesar Rp. 8.000/kg
beras.
Kebebasan memilih merupakan faktor yang sangat
penting karena pilihan dengan informasi lengkap
(informed consent) merupakan hak seorang konsumen. Jika
hak ini dicuri atau direnggut oleh seorang produsen
maka produsen tersebut bersalah di hadapan hukum.
Konsep ini juga merupakan prinsip fundamental dalam
hukum kedokteran, dimana pasien boleh memilih perawatan
(medical procedure) manapun yang ia inginkan, bahkan
termasuk perawatan yang merugikan kesehatannya. Poin
pentingnya adalah pilihan pasien tersebut dibuat dengan
informasi yang lengkap sehingga ia mengetahui
konsekuensi dari pilihan tersebut.
3.4.4.3 Kartel menyebabkan kerugian ekonomi
terhadap konsumen, pelaku usaha, dan
kesejahteraan umum
The Organisation for Economic Co-operation and Development
(“OECD”) melaporkan bahwa 16 (enam belas) kartel global
yang terdeteksi menyebabkan hilangnya efisiensi ekonomi
Universitas Indonesia
90
dalam perdagangan lebih dari US$ 55 milyar.116 Dengan
kata lain, hak ekonomi konsumen global sebesar US$ 55
milyar dicuri atau ditipu oleh pelaku kartel. OECD juga
menyatakan bahwa kartel merupakan bentuk pelanggaran
paling buruk dari hukum persaingan usaha.117
Kementerian Perkembangan Ekonomi (Ministry of Economic
Development) Selandia Baru dalam laporan Regulatory Impact
Assessment tentang dasar kriminalisasi kartel di
Selandia Baru pada awal tahun 2010 menjelaskan bahwa
kartel merupakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya
efisiensi ekonomi.118 Harga pasar/kompetitif barang
dan/atau jasa tidak tercipta karena pelaku usaha
terkait meniadakan kompetisi diantara mereka. Umumnya
harga yang tercipta dari kartel jauh lebih tinggi dari
harga pasar/kompetitif karena pelaku usaha terkait
ingin meraup marjin keuntungan yang lebih besar dari
penjualan per satuan produk dan/jasa mereka. Dampak
buruk ini tidak hanya merugikan konsumen, namun juga
pelaku usaha lain (baru), persaingan, kualitas barang,
116 OECD 2006, Hard Core Cartels – Third Report on the Implementation of the1998 OECD Recommendation, dalam OECD Journal of Competition Law and Policy,Vol 8 no 1.
117 R. Hewitt Pate, Anti-cartel Enforcement: The Core Antitrust Mission,disampaikan kepada the British Institute of International and Comparative Lawpada Third Annual Conference on International and Comparative Competition Law(May 16, 2003), Lihat:http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/201199.htm (kunjunganterakhir tanggal 20 Mei 2010).
118 Manatu Ohanga,op.cit., hal. 18.
Universitas Indonesia
91
dan terhadap semangat inovasi dan pengembangan
teknologi.
Dampak buruk ini nampaknya juga merupakan dasar
kriminalisasi kartel jika merujuk pada UU No.5/1999.
Pada bagian menimbang UU No.5/1999 dijelaskan bahwa:
a. pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada
terwujudnya kesejahteraan rakyat.
b. demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya
kesempatan yang sama bagi setiap warga negara
untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan
pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha
yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya
ekonomi pasar yang wajar.
c. setiap orang yang berusaha di Indonesia harus
berada dalam situasi persaingan yang sehat dan
wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya
pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha
tertentu.
Pasal 3 UU No.5/1999 menyatakan:
“Tujuan pembentukan undang-undang ini adalahuntuk:
a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan
efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu
upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui
pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga
Universitas Indonesia
92
menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha
yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha
menengah, dan pelaku usaha kecil;
c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku
usaha; dan
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam
kegiatan usaha.”
Selanjutnya, bagian penjelasan umum UU No.5/1999
menyatakan:
“Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan
kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan
keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan
kepentingan umum dengan tujuan untuk: menjaga
kepentingan umum dan melindungi konsumen;
menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui
terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan
menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama
bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang
ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan
efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha
dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan
kesejahteraan rakyat.”
Universitas Indonesia
93
Kartel membuat para pelaku usaha yang terlibat
didalamnya kehilangan insentif untuk berinovasi. Pelaku
usaha, dalam stuktur pasar kompetitif harus memenangkan
persaingan dengan mengurangi harga, meningkatkan
kualitas, atau mendiversifikasi produk. Tentunya,
pengurangan harga dan peningkatan kualitas tersebut
dengan asumsi semua faktor produksi tetap sama (ceteris
paribus), yang artinya dilakukan secara jujur, misalnya:
bukan dengan jual rugi. Dalam skenario tersebut, pelaku
usaha didorong secara jujur untuk memenangkan
persaingan dengan cara berpikir keras untuk berinovasi.
Inovasi tersebut diwujudkan dalam bentuk, salah
satunya, diversifikasi produk dan peningkatan
penelitian dan pengembangan (research & development).
Bayangkan jika produk elektronik untuk telekomunikasi
hanya dikuasai oleh perusahaan telegram melalui kartel,
maka mungkin saja telepon tidak akan
diciptakan/ditemukan. Sama halnya dengan persaingan
antara produk telekomunikasi telepon genggam melalui
jaringan Global System for Mobile Communication (“GSM”) dengan
Voice over Internet Protocol (“VoIP”), seperti Skype.119
119 Skype adalah sebuah program komunikasi dengan teknologiP2P (peer to peer). Program ini merupakan program bebas (dapatdiunduh gratis) dan dibuat dengan tujuan penyediaan saranakomunikasi suara (voice) berkualitas tinggi yang murah berbasiskaninternet untuk semua orang di berbagai belahan dunia. PenggunaSkype dapat berbicara dengan pengguna Skype lainnya dengan gratis,menghubungi telepon tradisional dengan biaya (skypeOut), menerimapanggilan dari telepon tradisional (skypeIn), dan menerima pesansuara.
Universitas Indonesia
94
Singkatnya, layanan telekomunikasi berbentuk VoIP yang
jauh lebih efisien dan murah dibandingkan dengan GSM
tidak akan diciptakan jika ada kartel dalam industri
telekomunikasi.
Senada dengan pendapat di atas, RIA tentang
kriminalisasi kartel di Selandia Baru menjabarkan
dampak buruk kartel sebagai berikut.120
a. Kartel menyebabkan kerugian terhadap ekonomi
dan konsumen. Konsumen yang dimaksud di sini
adalah konsumen dalam arti umum, yang termasuk
pelaku usaha pesaing, dan pelaku usaha yang
bukan konsumen akhir (end-consumer), dan konsumen
akhir.
b. Kartel menciptakan hilangnya efisiensi ekonomi
karena mematikan kinerja pasar. Dalam pasar
kompetitif, harga barang dan jasa ditetapkan
agar sumber daya dialokasikan kepada produksi
barang dan jasa yang mempunyai nilai paling
tinggi untuk konsumen. Seorang kartelis yang
sukses menaikkan harga di atas tingkat harga
pasar dan mengurangi permintaan dan oleh
karenanya mengurangi produksi barang dan jasa.
Akibatnya, sumber daya alam tidak dialokasikan
ke sektor yang paling bermanfaat atau
menguntungkan bagi konsumen (inefisiensi
alokatif). Kartel juga melindungi anggotanya
120 Manatu Ohanga, op.cit., hal. 17-19.
Universitas Indonesia
95
dari resiko kehilangan pangsa pasar akibat
persaingan, oleh karenanya mengurangi insentif
bagi mereka melakukan inovasi untuk mengurangi
biaya atau meningkatkan kualitas produk mereka
supaya bisa mempertahankan atau memenangkan
pangsa pasar. Kartel melindungi pelaku usaha
yang tidak efisien dan menghilangkan efisiensi
produksi.
c. Kegiatan usaha yang dikartelisasi juga menjadi
daya tarik bagi investasi karena kegiatan usaha
tersebut lebih menguntungkan daripada kegiatan
usaha dalam pasar kompetitif. Dalam disiplin
ilmu ekonomi, hal ini dinamakan hilangnya
efisiensi dinamis (dynamic efficiency). Dampak buruk
yang praktis dari hilang efisiensi dinamis
adalah investasi yang seharusnya ditanamkan
dalam sektor usaha lain yang lebih kompetitif
dan lebih bermanfaat dialihkan ke bidang usaha
yang dikartelisasi tersebut. Hal ini
menyebabkan efek rentetan seperti (i)
inefisiensi faktor produksi, misalnya bahan
baku dialihkan ke sektor usaha lain yang tidak
bermanfaat; (ii) penutupan lapangan kerja di
sektor usaha kompetitif; (iii) hilangnya
potensi lapangan kerja, dan (iv) berhentinya
atau berkurangnya inovasi dalam sektor usaha
kompetitif sehingga barang dan/atau jasa yang
Universitas Indonesia
96
diproduksinya semakin mahal dan menurun
kualitasnya.
d. Kartel menyebabkan rasa sakit (harm) dan
kerusakan (damage) langsung kepada konsumen
melalui transfer kekayaan dari konsumen kepada
kartelis. Jika konsumen membeli barang atau
jasa dari kartel, konsumen tersebut membayar
lebih daripada yang seharusnya dibayarkannya
jika pasar tersebut bersifat kompetitif. Jika
konsumen mengetahui bahwa harga barang atau
jasa tersebut telah diatur melalui kartel,
bukan melalui mekanisme pasar, maka konsumen
tersebut tidak akan membayar sejumlah uang
tertentu untuk membeli barang atau jasa
tersebut. Namun, karena konsumen mengasumsikan
bahwa harga penjualan adalah harga pasar
kompetitif, mereka secara tanpa mengetahuinya
telah membantu produsen kartel mendapatkan
keuntungan berlebih yang dikeruk dari kantong
konsumen.
e. Meskipun (assuming arguendo) transfer kekayaaan
dari konsumen ke produsen dianggap netral dan
bukan suatu pelanggaran hukum, kartel tetap
menyebabkan dampak buruk, yaitu inefisiensi
ekonomi.
f. Kartel merupakan intervensi yang melawan hukum,
seperti halnya manipulasi dan insider trading
Universitas Indonesia
97
(distorsi terhadap pasar saham), penyelundungan
pajak (distorsi terhadap sistem pemungutan
pendapatan) dan pelanggaran terhadap sistem
hukum, seperti penghalangan proses hukum
(obstruction of justice).
Singkatnya, kartel memungkinkan para pelakunya untuk
menaikkan keuntungan mereka dengan membatasi atau
menghilangkan kompetisi yang memungkinkan harga produk
berada pada tingkat harga kompetitif. Kartel
menyebabkan rasa sakit (harm) dan kerusakan (damage)
dengan:
a. mengurangi output ekonomi;
b. melemahkan persaingan sebagai mekanisme yang
menentukan harga;
c. melemahkan kepercayaan dalam pasar;
d. menyebabkan hilangnya efisiensi alokatif,
produktif, dan dinamis;
e. memperlambat pertumbuhan produktifitas; dan
f. mendistorsi investasi dengan menciptakan kesan
bahwa kartel lebih menguntungkan bagi bisnis
daripada pasar yang tidak terdistorsi oleh kartel.
Untuk menjelaskan dampak buruk kartel secara lebih
rinci, Penulis akan memaparkan penjelasan tentang
hilangnya efisiensi akibat kartel berdasarkan disiplin
ilmu ekonomi di bawah ini.
i. Konsep biaya (Cost)
Universitas Indonesia
98
1. Fixed cost dan variable cost
Biaya total (total cost) sama dengan biaya tetap
ditambah biaya variabel. Biaya tetap (fixed cost) adalah
biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah
produksi, contohnya biaya barang modal, gaji pegawai,
bunga pinjaman, sewa gedung kantor. Biaya variabel
(variable cost) adalah biaya yang besarnya tergantung pada
tingkat produksi, contohnya upah buruh dan biaya bahan
baku.
TC = TFC + TVC
di mana:
TC = biaya total jangka pendek
TFC = biaya tetap jangka pendek
TVC = biaya variabel jangka pendek
TFC bernilai konstan yang artinya bahwa besarnya
biaya tetap tidak tegantung pada jumlah produksi.
Sementara TVC menunjukan hubungan terbalik antara
tingkat produktivitas dengan besarnya biaya.
2. Average Cost (AC)
Biaya rata-rata adalah biaya yang harus dikeluarkan
untuk memproduksi satu unit output. Besarnya biaya
rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output.
Karena dalam jangka pendek TC=TFC+TVC, maka biaya rata-
rata (average cost) sama dengan biaya tetap rata-rata
(average fixed cost) ditambah biaya variabel rata-rata
(average variable cost).
Universitas Indonesia
99
di mana:
AC = biaya rata-rata jangka pendek
AFC = biaya tetap rata-rata jangka pendek
AVC = biaya variabel rata-rata jangka pendek
Nilai AFC akan semakin menurun bila produksi
ditambah. Nilai AVC pada tahap awal produksi akan
mengalami penurunan, namun pada tahap penggunaan
kapasitas secara penuh, nilai AVC akan mulai meningkat.
Pola ini berkaitan dengan hukum the Law of Diminishing
Return.121
3. Marginal Cost (MC)
121 Dalam disiplin ilmu ekonomi, the diminishing returns merujukpada produksi marjinal dari sebuah faktor produksi mulai berkurangsecara bertahap ketika faktor produksi bertambah. Menurut konsepini, dalam sistem produksi dengan input yang tetap (fixed) dantidak tetap (variable) (misalnya ukuran pabrik dan jumlah tenagakerja), akan terdapat satu titik dimana penambahan setiap unitvariable input (contoh: jumlah jam buruh) akan menghasilkan outputyang semakin kecil, juga mengurangi tingkat produktivitas setiappekerja. Sebaliknya, untuk produksi setiap unit akan diperlukanbiaya yang lebih besar dan semakin meningkat seiring dengan jumlahproduksi yang bertambah. Singkatnya, the law of diminishing returnmenyatakan “bahwa kita akan mendapatkan semakin sedikit dansemakin sedikit output tambahan ketika kita menambah dosis inputsementara fixed inputs tetap. Dengan kata lain, produksi marjinaldari setiap input unit akan berkurang karena jumlah input tersebutbertambah sementara input lain tetap (konstan).
Universitas Indonesia
100
Yang paling penting di antara semua komponen biaya
adalah konsep biaya marjinal (MC), yakni naiknya biaya
total yang disebabkan oleh produksi satu unit
output. Sebagai contoh diumpamakan sebuah perusahaan
menghasilkan 1.000 unit output per periode dan
memutuskan untuk menaikkan tingkat produksi menjadi
1.001. Menghasilkan satu unit ekstra akan meningkatkan
biaya dan kenaikan tersebut (artinya, biaya memproduksi
unit yang ke 1001 itu) merupakan biaya marjinal.
ii. Efisiensi ekonomi
Dalam struktur pasar persaingan sempurna kinerja
pasar akan optimal. Optimal dalam hal ini adalah
efisiensi yang dihasilkan oleh pasar tersebut, yaitu
efisiensi alokatif dan efisiensi produktif. Struktur
pasar persaingan sempurna merupakan satu-satunya pasar
dimana kedua efisiensi tersebut tercapai sekaligus.
Efisiensi alokatif adalah suatu kondisi dimana
pengalokasian sumber daya telah sesuai dengan
peruntukannya yang diindikasikan oleh kondisi ketika
tingkat harga (Price=P) sama dengan biaya marjinal
secara ekonomi (Marginal Cost=MC). Sedangkan efisiensi
produktif adalah suatu kondisi dimana perusahaan
memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang paling
rendah atau tingkat produksi yang paling efisien, yang
diindikasikan oleh kondisi dimana tingkat produksi
Universitas Indonesia
101
berada pada tingkat biaya rata-rata per unit (Average
Cost=AC) yang paling rendah.
Efisiensi alokatif juga terkait dengan apakah
faktor produksi sudah ditempatkan di ruang dan waktu
dimana hasil produksi dibutuhkan, sementara efisiensi
produktif terkait erat dengan efisiensi penggunaan 4
(empat) faktor produksi untuk menghasilkan barang
dengan harga paling murah dan kualitas yang paling
baik. Misalnya, kota A mempunyai tingkat permintaan 100
sepatu per bulan dan pabrik sepatu di kota A mampu
menghasilkan 200 sepatu dalam kondisi produksi yang
optimal, sementara kota B mempunyai tingkat permintaan
200, namun pabtrik sepatu hanya mampu memproduksi 100
sepatu dalam kondisi produksi yang optimal. Asumsinya
adalah (i) pabrik sepatu di kota A tidak mengekspor
sepatunya karena biaya yang tinggi; dan (ii) jarak kota
A dan B tidak jauh sehingga biaya transportasi tidak
terlalu tinggi. Jika struktur seperti ini
dipertahankan, maka terjadi inefisiensi alokatif
walaupun pabrik sepatu di kota A bisa memproduksi
sepatu dengan tingkat efisiensi produktif yang tinggi.
Alasannya adalah karena sepatu yang diproduksi sebesar
200 buah tidak akan habis diserap permintaan pasar,
sehingga pada bulan berikutnya pabrik sepatu di A tidak
akan berproduksi; dan harga sepatu juga akan bertambah
murah. Akibatnya, penghasilan pabrik sepatu A berkurang
dan tingkat produksinya juga akan berkurang (baik
Universitas Indonesia
102
kualitas maupun kuantitas) untuk menyesuaikan diri
dengan kondisi pasar.
Dengan demikian, dalam jangka panjang, di dalam
pasar persaingan sempurna akan tercapai kondisi
efisiensi ekonomi (economic efficiency) yaitu ketika
efisiensi alokatif dan efisiensi produktif tercapai,
yang dapat ditunjukkan oleh persamaan di bawah ini:
Keterangan
P = Price
MC = Marginal Cost
ACMin =Average Cost Minimum
SRAC = Short-Run Average Cost
LRAC = Long-Run Average Cost
Secara grafis kondisi tersebut dapat ditunjukkan
dalam gambar I. Secara sosial, kinerja yang dihasilkan
oleh struktur pasar persaingan sempurna juga sangat
baik (desirable). Dengan tercapainya efisiensi alokatif
dan efisiensi produktif, maka kesejahteraan (welfare)
pasar juga akan optimal. Kesejahteraan pasar diukur
dari keuntungan yang diperoleh konsumen atau yang
sering disebut dengan surplus konsumen (consumer
surplus), dan keuntungan yang diperoleh produsen atau
disebut dengan surplus produsen (producer surplus).
Gambar I122
Keseimbangan Jangka Panjang Pasar Persaingan Sempurna122 Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, et.al., op.cit.,
hal 37
Universitas Indonesia
103
Keterangan
SATC = Short-run Average Total Cost
LATC = Long-run Average Total Cost
Surplus konsumen adalah selisih antara harga
maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen (willingness
to pay) dengan harga yang benar-benar dibayar oleh
konsumen. Surplus produsen adalah selisih antara harga
minimum yang bersedia diterima oleh produsen (sebesar
biaya marjinalnya) dengan harga yang benar-benar
diterima oleh produsen. Total surplus yang ada di pasar
adalah penjumlahan surplus konsumen dan produsen. Hal
ini dapat dilihat pada gambar II.
Apabila struktur pasar bersifat tidak sempurna
(imperfect market), maka akan terjadi inefisiensi ekonomi.
Terjadinya inefisiensi ekonomi disebut sebagai
kegagalan pasar (market failure) . Selain dari bentuk
pasar yang tidak sempurna, kegagalan pasar juga terjadi
karena adanya eksternalitas, barang publik, dan
informasi yang tidak simetris.
Universitas Indonesia
104
Singkatnya, efisiensi ekonomi tercapai ketika
permintaan (demand) dan penawaran (supply) berada pada
titik ekuilibrium karena efisiensi alokatif dan
efisiensi produktif tercapai.
Gambar II123
Kesejahteraan di Pasar
Keterangan
PS = Producer surplus
CS = Consumer surplus
Gambar III
Deadweight Loss: Hilangnya surplus konsumen
123 Ibid, hal 38.
Universitas Indonesia
105
Gambar III menunjukkan bagaimana pelaku usaha
mengambil surplus konsumen dan mengubahnya menjadi
surplus produsen. Ketika jumlah produksi dikurangi,
maka akan terjadi kelangkaan kuantitas barang di pasar
dan kelangkaan tersebut menyebabkan naiknya harga
barang. Gambar III menunjukkan terjadinya deadweight
loss.124 Deadweight loss tersebut terjadi pada bagian consumer
surplus yang diambil oleh produsen melalui peningkatan
harga (artinya, marjin harga untuk produk dengan
124 Dalam disiplin ilmu ekonomi, deadweight loss (atau disebutjuga inefisiensi alokatif) adalah kehilangan efisiensi ekonomiyang terjadi karena ekuilibrium untuk barang atau jasa tidakberada pada Pareto optimal. Dengan kata lain, yang terjadi adalah (i)orang dengan keuntungan marginal yang lebih besar dari biayamarginal tidak membeli produk, atau (ii) orang dengan biayamarginal yang lebih besar dari keuntungan marginal membeli produk.
Universitas Indonesia
106
kualitas yang sama dan pada waktu yang sama lebih
tinggi dari harga pasar).
Selanjutnya, Gambar III menunjukkan adanya
pertentangan kepentingan ekonomi hukum antara produsen
dengan konsumen. Seperti yang telah dijelaskan di atas
(Bab II, Poin 2.2 (A) tentang kriteria penentuan tindak
pidana), salah satu kriteria penentuan suatu perbuatan
sebagai perbuatan pidana adalah penyelesaian
pertentangan kepentingan-kepentingan hukum. Ketika
suatu pertentangan kepentingan hukum tertentu
membutuhkan penyelesaian yang efektif maka hukum pidana
menjadi jawaban yang efektif. Jika kita mengaitkan
konsep tersebut dengan Gambar III maka dapat
disimpulkan bahwa pertentangan kepentingan ekonomi
antara produsen dan konsumen mempersyaratkan kehadiran
hukum pidana di dalamnya. Selain itu, dampak dari
kartel yang sangat buruk berupa rasa sakit (harmful)
semakin memperkuat pendapat bahwa kartel harus
dikriminalisasi. Faktor lain yang menguatkan pendapat
bahwa kartel harus dikriminalisasi adalah sangat tidak
berimbangnya posisi produsen (yang lebih kuat) dan
konsumen (yang jauh lebih lemah).
Universitas Indonesia
107
BAB IVSTRATEGI PRISONER’S DILEMMA: DILEMA PENDEKATAN SANKSIPIDANA PENJARA, SANKSI PIDANA DENDA, DAN/ATAU GANTIRUGI PERDATA
“Grant I may never prove so fond,To trust man on his oath or bond.”-William Shakespeare
Timon of Athens, I. ii. 64
Pada Bab II telah dijabarkan dasar kriminalisasi
suatu perbuatan dan pada Bab III telah dijabarkan dasar
kriminalisasi kartel. Penjelasan Bab IV menggunakan
asumsi bahwa (i) kartel adalah suatu perbuatan dan/atau
perjanjian yang memenuhi kualifikasi/kriteria suatu
perbuatan yang dikriminalisasi (lihat penjelasan Bab II
tentang Dasar Kriminalisasi Suatu Perbuatan) dan (ii)
kartel adalah perbuatan yang dikriminalisasi
berdasarkan perspektif utilitarianisme (yaitu
menyebabkan kerugian, rasa sakit, ketidaksenangan, dan
ketidakpuasan manusia). Penulis menggunakan perspektif
utilitarianisme dalam melakukan analisis terhadap
dilema pendekatan sanksi pidana penjara, sanksi pidana
denda, dan/atau ganti rugi perdata. Implikasinya adalah
selama efektifitas dan efisiensi tercapai, maka hukum
sudah mencapai tujuannya. Analisis yang dilakukan dalam
Bab IV menitikberatkan pada tingkat efektifitas dan
efisiensi sanksi.
Universitas Indonesia
108
Strategi prisoner’s dilemma menggambarkan tarik-menarik
antara penentuan sanksi pidana penjara, denda, dan
ganti rugi perdata atas kartel. Strategi ini sangat
berguna dalam menerapkan asas ultimum remedium karena
mampu mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi sanksi
sehingga otoritas persaingan usaha maupun legislator
mampu menentukan dengan timbangan yang lebih akurat
sanksi mana yang dipakai.
Penulis akan menganalisis apakah penyelesaian
pidana merupakan penyelesaian yang paling efektif dan
efisien dibandingkan dengan penyelesaian lain untuk
memberikan perlindungan yang cukup terhadap kepentingan
masyarakat. Strategi prisoner’s dilemma menunjukkan tarik-
menarik antara tingkat efektifitas dan efisiensi sanksi
pidana penjara, sanksi pidana denda, dan ganti rugi
perdata sehingga kedinamisan penetapan sanksi atas
kartel terlihat jelas. Analisis ini akan menggambarkan
bagaimana dan kapan sanksi pidana penjara, sanksi
pidana denda, dan ganti rugi perdata digunakan. Menurut
Penulis, konsep “bagaimana dan kapan” tersebut mampu
menjawab pertanyaan legislator atau otoritas persaingan
usaha di Indonesia tentang penetapan sanksi.
Secara umum, Bab IV membahas tentang strategi
prisoner’s dilemma dan tarik ulur penyelesaian pidana
penjara, pidana denda dan/atau gugatan ganti rugi
perdata.125 Selanjutnya, Penulis akan menjelaskan secara
125 Berdasarkan Pasal 10 KUHP, sanksi pidana meliputi sanksipidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan.
Universitas Indonesia
109
rinci tentang (i) strategi prisoner’s dilemma, (ii)
sejarah penerapannya di Amerika Serikat, (iii) logika
penerapan strategi prisoner’s dilemma, (iv) kaitan tarik
ulur sanksi pidana penjara, pidana denda dan/atau ganti
rugi perdata dalam strategi prisoner’s diemma, (v)
bagaimana strategi prisoner’s dilemma bisa diterapkan untuk
mengakomodasi atau memungkinkan terpenuhinya fungsi
hukum pidana, (vi) kerancuan dan/atau absurditas
penentuan sanksi terhadap kartel berdasarkan UU
No.5/1999, dan (vii) analisis komparatif tentang cara
merumuskan kebijakan sanksi terhadap kartel untuk
meningkatkan efek jera di Amerika Serikat.
4.1 Prisoner’s Dilemma
4.1.1 Sejarah penentuan sanksi atas kartel di
Amerika Serikat
Bagan pola perubahan sanksi dalam hukum persaingan usaha Amerika
Serikat
Act/kebijakan dan tahun Sanksi pidana penjara dan pidana
denda
Sherman Act 1890 Sanksi pidana denda USD 5.000
dan penjara selama 1 (satu)
tahunSection 4 Clayton Act 1914 Penghitungan ganti rugi perdata
adalah tiga kali lipat dari
kerugian aktual atau treble damages
Universitas Indonesia
110
Amandemen Sherman Act pada
tahun 1955
Sanksi pidana denda USD 50.000
dan penjara selama 1 (satu)
tahunThe Antitrust Procedures and
Penalties Act 1974 menentukan
kejahatan persaingan usaha
sebagai felony (kejahatan
berat)
Sanksi pidana denda USD 1 juta
untuk korporasi dan USD 100.000
untuk individu dan penjara
selama 3 (tiga) tahun
Criminal Fine Enforcement Act
1984
USD 250.000 ribu untuk individu
Sentencing Reform Act dengan
lampiran Sentencing Guidelines
dan Criminal Fines Improvement
Act 1987.
Penghitungan sanksi pidana denda
adalah dua kali lipat dari
kerugian aktual atau double
damages
Berdasarkan Title 18 United
States Code § 3571(d):
Title 15 United States Code
§ 1 pada tahun 1990
Sanksi pidana denda adalah USD
10 juta untuk korporasi dan USD
350.000 untuk individuCorporate Leniency Program dari
Department of Justice 1993
Penghitungan ganti rugi perdata
adalah tigakali lipat dari
kerugian aktual atau treble damages
Korporasi dan individual bisa
Universitas Indonesia
jumlah sanksi pidana denda =
keuntungan yang didapatkan atau
kerugian yang diderita X 2
jumlah total ganti rugi perdata =
keuntungan yang didapatkan atau
kerugian yang diderita X 3
111
dibebaskan dari tuntutan pidana
penjara jika mereka adalah yang
pertama kali maju, mengaku
salah, dan bekerjasama dengan
Antitrust Division untuk membongkar
kejahatan persaingan usaha
tersebut. Pembebasan tuntutan
pidana penjara hanya berlaku
untuk pihak yang pertama kali
maju.
Antitrust Criminal Penalties
Enforcement and Reform Act 2004
Berdasarkan Section 215 Antitrust
Criminal Penalties Enforcement and Reform
Act 2004, batas maksimum sanksi
pidana denda diubah menjadi USD
100 juta untuk korporasi dan USD
1 juta untuk individu.
Treble damages dalam gugatan ganti
rugi perdata dihapuskan sehingga
perhitungan ganti rugi perdata
adalah sejumlah kerugian aktual
atau single civil damages.
dan
Korporasi dan individual bisa
dibebaskan dari tuntutan pidana
penjara jika mereka maju,
Universitas Indonesia
112
mengaku salah, dan bekerjasama
dengan Antitrust Division untuk
membongkar kejahatan persaingan
usaha tersebut. Pembebasan
tuntutan pidana penjara berlaku
untuk yang maju pertama kali,
kedua kali dan seterusnya.
i.Sebelum 1993
Section 1, 2, dan 3 Sherman Act menerapkan 2 (dua)
sanksi untuk kartel, yaitu pidana penjara dan pidana
denda. Selama beberapa dekade, Departemen Hukum
Persaingan Usaha atau Antitrust Division Amerika Serikat
mempertimbangkan apakah kartel dihukum dengan pidana
penjara atau pidana denda. Sejarahnya, penerapan sanksi
pidana penjara terhadap kartel dimulai dari perumusan
ketentuan dalam Sherman Act pada tahun 1890 (yang
merupakan peraturan perundang-undangan Amerika Serikat
pertama tentang persaingan usaha), dimana sanksi denda
sebesar USD 5.000 (lima ribu) dan penjara selama 1
(satu) tahun diterapkan sebagai sanksi maksimum bagi
pelanggaran hukum persaingan usaha. Sejalan dengan
waktu, kongres Amerika Serikat memutuskan untuk
memperberat sanksi pidana penjara dalam Sherman Act. Pada
tahun 1955, kongres menaikkan sanksi denda maksimum
Universitas Indonesia
113
menjadi USD 50.000 untuk setiap pelanggaran.126
Selanjutnya, Undang-Undang Prosedur dan Sanksi
Antitrust atau The Antitrust Procedures and Penalties Act tahun
1974 menentukan bahwa pelanggaran Sherman Act
ditingkatkan menjadi kejahatan berat (felonies)127 dan
menaikkan pidana denda menjadi USD 1 juta untuk
korporasi dan USD 100.000 untuk individu, dan menaikkan
pidana penjara menjadi tiga tahun. Pada tahun 1984,
diundangkan Undang-Undang Pelaksanaan Pidana Denda atau
Criminal Fine Enforcement Act menaikkan pidana denda maksimum
untuk individu menjadi USD 250.000. Pada tahun yang
sama, diundangkan Undang-Undang Reformasi Sanksi atau
Sentencing Reform Act bersamaan dengan Pedoman Sanksi atau
Sentencing Guidelines yang diikuti dengan diundangkannya
Undang-Undang Peningkatan Pidana Denda atau Criminal Fines
Improvement Act pada tahun 1987. Criminal Fines Improvement Act
126 Glenn Harrision dan Matthew Bell, Recent Enchancements inAntitrust Criminal Enforcement: Bigger Sticks and Sweeter Carrots, HoustonBusiness and Tax Law Journal, 2006, 6 Hous. Bus. & Tax. L.J. 207.
127 Felony adalah kejahatan serius berdasarkan sistem Anglo-Saxon. Kata felony berasal dari sistem Hukum Common Law Inggris.Felony awalnya merupakan kejahatan yang melibatkan penyitaanterhadap tanah dan benda seseorang. Amerika Serikat mendefiniskanfelony sebagai kejahatan yang bisa dihukum dengan hukuman mati ataupenjara lebih dari satu tahun (Lihat 18 U.S.C. § 3559 dihttp://www.law.cornell.edu/uscode/18/3559.html (kunjungan terakhirtanggal 7 Juni 2010). Berdasarkan Pasal 18 United States Code § 3559,kejahatan-kejahatan yang merupakan felony termasuk, namun tidakterbatas pada, pembunuhan (murder), pemerkosaan (rape),penganiayaan berat (aggravated assault), dan/atau penganiayaan(battery), pembakaran (arson), pencurian dengan memasuki rumah ataupekarangan (burglary), penjualan obat-obatan terlarang, danpencurian benda/barang (robbery).
Universitas Indonesia
114
mengotorisasi sanksi alternatif yang dikodifikasi pada
Title 18 United States Code (“USC”) § 3571(d) yang
menyatakan:
“(d) Alternative Fine Based on Gain or Loss. If any person derives
pecuniary gain from the offense, or if the offense results in pecuniary
loss to a person other than the defendant, the defendant may be
fined not more than the greater of twice the gross gain or twice the
gross loss, unless imposition of a fine under this subsection would
unduly complicate or prolong the sentencing process.”
Terjemahan bebasnya:
“(d) Denda alternatif berdasarkan keuntungan atau
kerugian. Jika seseorang mendapatkan keuntungan
finansial (uang) dari kejahatannya, atau jika
kejahatan tersebut mengakibatkan kerugian finansial
(uang) kepada seseorang selain dari terdakwa, maka
terdakwa bisa dikenakan ganti rugi perdata tidak
lebih dari 2 (dua) kali keuntungan uang yang ia
dapatkan atau 2 (dua) kali kerugian uang yang
dialami oleh orang lain, kecuali jika penerapan
ganti rugi perdata berdasarkan sub-bagian ini akan
secara tidak pantas/tepat mempersulit atau
memperpanjang proses persidangan.”
Sejak tahun 1987, Antitrust Division telah bergantung
pada U.S.C. § 3571(d) untuk menegosiasikan sanksi
Universitas Indonesia
115
pidana denda melebihi USD 10 juta, angka mana merupakan
sanksi denda maksimum berdasarkan Sherman Act. Pada
kenyataannya, Antitrust Division berhasil mendapatkan nilai
denda sejumlah lebih dari USD 100 juta, termasuk rekor
sanksi denda dari Department of Justice sebesar USD 500 juta
terhadap F. Hoffman-La Roche terkait dengan produk
vitamin. Walaupun Antitrust Division berhasil mendapatkan
nilai denda melebihi jumlah denda maksimum yang
ditentukan Sherman Act, keberhasilan Antitrust Division ini
hanya terbatas pada kasus-kasus yang diselesaikan
melalui plea agreement atau peringanan hukuman yang
diberikan karena tersangka/terdakwa mengaku bersalah.128
Pada tahun 1990, kongres Amerika Serikat
meningkatkan kembali sanksi pidana dengan menaikkan
sanksi denda menjadi USD 10 juta untuk korporasi dan
USD 350.000 untuk individu.129 Pada dasarnya, Sentencing
Guidelines menentukan dua cara untuk menghitung pidana
denda untuk korporasi.130
128 Glenn Harrision dan Matthew Bell, op.cit
129 Title 15 United States Code § 1 (2000).
130 Lihat U.S. Sentencing Guidelines Manual § 2B1.1(b)(9)(C) (2004)(diamandemen tahun 2005). Berdasarkan Under § 8C2.4(a), sanksidenda minimum untuk korporasi adalah alternatif yang lebihmemberatkan di antara ketiga alternatif di bawah:
(1) Jumlah perhitungan berdasarkan bagan § 8C2.4(d)terkait dengan tingkat kejahatan yang ditentukanberdasarkan under § 8C2.3
(2) Jumlah keuntungan uang yang didapatkan organisasitersebut; atau
(3) Kerugian uang yang disebabkan oleh kejahatanorganisasi tersebut sejauh kerugian tersebut disebabkansecara sengaja, secara tahu, atau secara tidak berhati-hati.
Universitas Indonesia
116
Program amnesti131 Antitrust Division atau corporate leniency
program yang dimulai pada tahun 1978.132 Kebijakan pra-
1993 menentukan bahwa pelaku usaha pertama yang
menyerahkan diri/mengaku bersalah dan membantu Antitrust
Division untuk membongkar kejahatan persaingan usaha
tidak dituntut dan dibebaskan dari gugatan ganti rugi
perdata, jika beberapa kriteria berikut dipenuhi.
Pelaku usaha yang memohon amnesti akan dimaafkan hanya
jika pelaku usaha tersebut mengaku bersalah sebelum
Antitrust Division mengetahui aktivitas ilegal atau sebelum
Antitrust Division melakukan investigasi. Kebijakan pra-1993
tidak membahas tentang keringanan hukuman terhadap
pejabat, direktur dan pekerja korporasi.
ii. Corporate Leniency Program 1993
Pada tahun 1993, Antitrust Division mengeluarkan
kebijakan Corporate Leniency Program yang pada dasarnya
bertujuan untuk mendeteksi kartel dengan mendorong para
131 Istilah amnesti yang digunakan dalam Skripsi ini bukanmerupakan istilah amnesti seperti yang dikenal dalam Pasal 14 UUD1945. “Amnesti” dalam Skripsi ini berarti pemaafan (pengampunan)yang diberikan kepada pelaku usaha yang membantu dan bekerja samadengan otoritas persaingan usaha.
132 Robert E. Bloch, Program Amnesti The Antitrust Division,dipresentasikan pada the American Bar Association's Section of Antitrust Law'sCriminal Antitrust Law and Procedure Workshop (Feb. 23-24, 1995). Lihat dihttp:// www.mayerbrownrowe.com/publications/article.asp?id=841&nid=6 (kunjungan terakhir 29 Mei 2010). Sejak tahun 1978sampai tahun 1993, 17 korporasi telah mendaftarkan permohonanuntuk amnesti korporasi dan 10 di antaranya mendapatkan amnestitersebut.
Universitas Indonesia
117
kartelis untuk melaporkan aktivitas ilegal mereka
kepada pemerintah. Jika suatu pelaku usaha masuk dalam
Corporate Leniency Program dengan maju, mengaku bersalah,
dan membantu Antitrust Division dalam investigasinya, Antitrust
Division akan membebaskan mereka dari semua tuntuntan
pidana penjara yang terkait dengan keanggotaan pelaku
usaha tersebut dalam kartel.133 Namun, pengakuan
bersalah ini tidak meniadakan sanksi denda atau gugatan
perdata dari pihak yang dirugikan. Tidak
dimaafkannya/digugurkannya gugatan ganti rugi perdata
adalah kunci utama yang membedakan Corporate Leniency
Program 1993. Artinya, kartelis yang mengaku hanya
dimaafkan atas tanggung jawab pidana, namun tetap
dihukum untuk mengganti rugi perdata tiga kali lipat
atau treble damages.
Prosedur permohonan untuk masuk dalam Corporate
Leniency Program adalah sebagai berikut. Pertama, corporate
leniency program memberikan amnesti secara otomatis kepada
pelaku usaha yang melaporkan kegiatan persaingan usaha
ilegal sebelum investigasi dimulai (disebut “amnesti
A”) dengan syarat 6 kondisi berikut dipenuhi: (1)
Antitrust Division belum menerima informasi tentang
aktivitas ilegal dari sumber manapun; (2) segera
setelah ditemukan bukti permulaan, pelaku usaha133 Department of Justice Amerika Serikat, Corporate Leniency Policy
(1993). Lihat di http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0091.htm (kunjungan terakhir30 Mei 2010). Keringanan (leniency) artinya tidak ada tuntutanterhadap korporasi terlapor yang dimintakan pertanggungjawabanpidana.
Universitas Indonesia
118
bertindak sesegera mungkin untuk mengakhiri
keikutsertaannya dalam aktivitas tersebut; (3) pelaku
usaha secara jujur dan lengkap melaporkan aktivitas
tersebut dan membantu otoritas dalam penyelidikan; (4)
pengakuan tersebut merupakan perbuatan pelaku usaha,
dan bukan merupakan pengakuan dari individu (misalnya
yang bekerja untuk pelaku usaha); (5) pelaku usaha
merestitusi pihak-pihak yang dirugikan; dan (6) pelaku
usaha tidak memaksa pihak manapun untuk ikut serta
dalam aktivitas ilegal dan pelaku usaha tersebut bukan
pemimpin atau yang memulai aktivitas ilegal tersebut.
Kedua, kebijakan baru tersebut menentukan jika
suatu pelaku usaha mengaku bersalah setelah investigasi
dimulai, pelaku usaha tersebut masih bisa mendapatkan
amnesti (disebut “amnesti B”) jika Antitrust Division belum
menemukan bukti kuat (meyakinkan) yang memungkinkan
Antitrust Division memenangkan tuntutannya (likely to result in a
sustainable conviction), dengan syarat: (1) pelaku usaha
tersebut adalah pelaku usaha pertama yang mengaku
bersalah dan memenuhi syarat amnesti; (2) pada saat
melapor, Antitrust Division mempunyai bukti kuat (meyakinkan
yang memungkinkannya untuk memenangkan tuntutan; (3)
sesegera setelah ditemukan bukti tersebut, pelaku usaha
bertindak secepat dan seefektif mungkin untuk
mengakhiri keikutsertaannya dalam aktivitas ilegal
tersebut; (4) pelaku usaha tersebut secara jujur dan
lengkap melaporkan kegiatan tersebut dan bekerjasama
Universitas Indonesia
119
secara penuh dengan Antitrust Division dalam investigasi
(penyidikan dan penyelidikan); (5) pengakuan tersebut
merupakan perbuatan pelaku usaha, dan bukan merupakan
pengakuan dari individu (misalnya yang bekerja untuk
pelaku usaha); (6) pelaku usaha merestitusi pihak-pihak
yang dirugikan; (7) Antitrust Division menentukan (i) bahwa
memberikan keringanan kepada pihak lain adalah adil
mengingat sifat (nature) dari aktivitas ilegal tersebut,
(ii) peran pelaku usaha yang melapor dalam aktivitas
tersebut, dan (iii) kapan pelaku usaha tersebut mengaku
salah.
Dalam situasi dimana suatu korporasi sedang
diinvestigasi atas partisipasinya dalam kegiatan
persaingan usaha ilegal tidak memenuhi syarat amnesti A
dan amnesti B dan (ii) korporasi tersebut menemukan
keikutsertaan dalam pejabat atau pekerjanya dalam
aktivitas persaingan usaha ilegal lainnya (yang tidak
diketahui oleh Antitrust Division), pelaku usaha tersebut
bisa memohon ‘amnesti plus’. Singkatnya, jika korporasi
tersebut memenuhi syarat untuk amnesti plus dan bekerja
sama dalam investigasi atas kasus baru dan berbeda,
Antitrust Division akan memberikan amnesti penuh kepada
korporasi tersebut dalam investigasi baru dan
memberikan keuntungan tambahan bagi korporasi tersebut
(contoh, pengurangan sanksi denda) dalam penghitungan
dendanya dalam plea agreement. Keuntungan ganda ini
merupakan insentif yang efektif bagi perusahaan untuk
Universitas Indonesia
120
maju dan mengaku bersalah berdasarkan inisiatifnya
sendiri.134
Pada tanggal 10 Agustus 1994, satu tahun setelah
diadopsinya Corporate Leniency Policy yang direvisi, Antitrust
Division mengumumkan kebijakan pendamping untuk individu.
Kebijakan ini berlaku untuk semua individu yang
membantu dan bekerjasama dengan Antitrust Division
berdasarkan inisiatifnya sendiri dan bukan merupakan
bagian dari pengakuan korporasi.135 Syarat diberikannya
amnesti individu adalah (i) individu tersebut harus
melaporkan aktivitas persaingan usaha ilegal yang belum
pernah diberitahukan kepada Antitrust Division (ii) individu
tersebut harus jujur dan bekerjasama secara penuh dan
kontinyu dalam proses investigasi (iii) individu
tersebut bukan merupakan inisiator atau pemimpin dari
aktivitas ilegal dan tidak memaksa pihak lain untuk
ikut serta dalam aktivitas tersebut.
iii. Antitrust Criminal Penalties Enforcement and Reform
Act 2004
134 Glenn Harrision dan Matthew Bell, op.cit
135 Antitrust Division, Department of Justice Amerika Serikat,Corporate Leniency Policy (1994). Lihat di http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/lencorp.htm (kunjunganterakhir 30 Mei 2010). Corporate Leniency Policy 1993 menentukan kondisiuntuk keringanan terhadap direktur, pejabat, dan pekerja, dalamkapasitasnya sebagai bagian dari korporasi, yang maju, mengakubersalah, dan membantu Antitrust Division dalam investigasi.
Universitas Indonesia
121
Section 215 dari Antitrust Criminal Penalties Enforcement and
Reform Act 2004 menaikkan sanksi pidana denda maksimum
untuk korporasi menjadi USD 100 juta,136 sementara
individu menjadi USD 1 juta.137 Sanksi pidana penjara
ditingkatkan menjadi maksimum 10 tahun.138 Act 2004 ini
juga menghapus treble damages dalam gugatan ganti rugi
perdata untuk pelaku usaha yang terlibat dalam
konspirasi penetapan harga yang pertama kali mengaku
dan mendapatkan amnesti dari Antitrust Division.
Sejak tahun 1993, program amnesti Antitrust Division
telah mencapai beberapa keberhasilan. Pertama, kenaikan
jumlah permohonan amnesti dari korporasi yang diajukan
kepada Antitrust Division. Selain itu, jumlah sanksi denda
terhadap kartel terlapor meningkat pesat.139 Investigasi
kartel sejak tahun 1997 melibatkan berbagai produk dan
industri dengan kegiatan persaingan usaha ilegal yang
merugikan lebih dari USD 10 milyar perdagangan Amerika
Serikat.140 Sebelum tahun 1997, Antitrust Division136 15 U.S.C. § 1 (2000).
137 Ibid.
138 Lihat § 215, 118 Stat. at 668.
139 Gary R. Spratling, Asisten Deputi Attorney GeneralAntitrust Division, Deparment of Justice Amerika Serikat, MakingCompanies An Offer They Shouldn't Refuse: The Antitrust Division's Corporate LeniencyPolicy-An Update, dipresentasikan pada the Bar Association of the District ofColumbia's 35th Annual Symposium on Associations and Antitrust 3 (Feb. 16,1999)/ Lihat di http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/2247.pdf. (kunjungan terakhir 30Mei 2010).
140 Scott D. Hammond (1), Direktur Criminal EnforcementAntitrust Division, Department of Justice Amerika Serikat, A
Universitas Indonesia
122
mendapatkan lebih kurang USD 29 juta per tahun melalui
sanksi denda.141 Pada tahun 1997 dan 1998, Antitrust Division
mendapatkan lebih dari USD 200 juta per tahun melalui
sanksi denda.142 Pada tahun 1999, Antitrust Division
mendapatkan jumlah mengagumkan sebesar USD 1,1 milyar
melalui sanksi denda, termasuk sanksi denda terbesar di
dalam sejarah Amerika Serikat sebesar USD 500 juta atas
kartel penetapan harga vitamin yang dilakukan oleh F.
Hoffman-La Roche.143 Oleh karena alasan di atas, program
amnesti Antitrust Division disebut sebagai metode paling
efektif untuk menghancurkan kartel.
Dalam selang waktu antara tahun 1991 sampai 2004,
ada tiga perkembangan penting dalam hukum persaingan
usaha Amerika Serikat terkait sanksi yang termaktub
dalam Peningkatan Sanksi Pidana Antitrust atau Antitrust
Criminal Penalties Enhancement and Reform Act 2004.144 Pertama,
Antitrust Division mulai menegosiasikan sanksi terhadap
Summary Overview of the Antitrust Division's Criminal Enforcement Program,dipresentasikan pada the New York State Bar Association 1 (Jan. 23, 2003).Lihat di http://www.justice.gov/atr/public/speeches/200686.htm(kunjungan terakhir 30 Mei 2010).
141 Ibid.
142 Ibid.
143 Scott D. Hammond (2), Direktur Criminal EnforcementAntitrust Division, Department of Justice Amerika Serikat, Detectingand Deterring Cartel Activity Through An Effective Leniency Program,dipresentasikan pada the International Workshop on Cartels 10 (Nov. 21-22,2000). Lihat di http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/9928.pdf(kunjungan terakhir 30 Mei 2010).
144 Glenn Harrision dan Matthew Bell, op.cit.
Universitas Indonesia
123
korporasi di atas sanksi maksimum yang ditentukan
Undang-Undang, yaitu Sherman Act, dengan menggunakan
ketentuan sanksi alternatif dalam 18 U.S.C. §
3571(d).145 Kedua, versi perubahan yang dibuat oleh
Antitrust Division yaitu Kebijakan Pengurangan Sanksi
terhadap Korporasi atau Corporate Leniency Policy
diperkenalkan pada tahun 1993. Ketiga, sebagai bagian
dari inisiatif kebijakan, Antitrust Division mulai membahas
tentang perlunya peningkatan sanksi pidana.146
4.1.2 Strategi Prisoner’s Dilemma dan tarik-menarik
antara sanksi pidana penjara, pidana denda
dan/atau ganti rugi perdata dalam skema
strategi prisoner’s dilemma
145 Berdasarkan ketentuan 18 U.S.C. § 3571 (d), pengadilantidak dipersyaratkan untuk menghitung keuntungan atau kerugianuang jika penghitungan tersebut akan mempersulit ataumemperpanjang proses penghukuman. Namun, pihak yang menegosiasikanhukuman harus menghitung secara rinci kerugian agar bisamenentukan potensi sanksi denda maksimum berdasarkan 3571 (d).
146 Gary R. Spratling, Asisten Deputi Attorney General, U.S.Department of Justice, The Trend Towards Higher Corporate Fines: It's a WholeNew Ball Game, dipresentasikan pada the American Bar Association's CriminalJustice Section's Eleventh Annual National Institute tentang White Collar Crime (Mar.7, 1997). Lihat dihttp://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/4011.pdf (kunjunganterakhir 29 Mei 2010); Gary R. Spratling Asisten Deputi AttorneyGeneral, U.S. Department of Justice, Are the Recent Titanic Fines in AntitrustCases Just the Tip of the Iceberg?, dipresentasikan pada the American BarAssociation's Criminal Justice Section's Twelfth Annual National Institute tentang WhiteCollar Crime (Mar. 6, 1998). Lihat dihttp://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/212581.pdf (kunjunganterakhir 29 Mei 2010).
Universitas Indonesia
124
Prisoner’s dilemma terjadi ketika polisi memisahkan 2
pihak ke ruang yang berbeda dan masing-masing diberikan
tawaran yang sama. Strategi ini efektif ketika 2 (dua)
pihak berkehendak untuk mengejar kepentingan masing-
masing dan bertindak secara rasional-egois (rationally
selfish manner).147 Tindakan rasional-egois ini
mengakibatkan kedua pihak tersebut berada pada situasi
yang lebih buruk dibandingkan dengan situasi dimana
mereka bekerjasama untuk mengejar kepentingan bersama
(daripada kepentingan masing-masing).148 Gambaran
prisoner’s dilemma klasik adalah sebagai berikut. Dua
orang tersangka melakukan kejahatan dan pelanggaran.
Polisi mempunyai bukti yang cukup untuk memenjarakan
kedua tersangka atas pelanggaran, namun polisi tidak
mempunyai cukup bukti untuk memenjarakan keduanya atas
kejahatan. Polisi menginterogasi kedua tersangka
tentang peran mereka atas kejahatan. Tidak ada satupun
tersangka yang mengaku, namun pengakuan dari salah
satunya cukup untuk memenjarakan kedua tersangka atas
kejahatan. Polisi berkeinginan untuk memenjarakan
setidaknya salah satu tersangka atas kejahatan. Oleh
karena itu, kedua tersangka diberikan tawaran yang
sama: ”Jika kamu mengaku dan membantu mencari bukti
untuk memenjarakan rekanmu, kamu dibebaskan dari
147 Christopher R. Leslie (1), Symposium The AntitrustEnterprise: Principle and Execution, Antitrust Amnesty, Game Theory, andCartel Stability, Journal of Corporation Law, 31 J. Corp. L. 453, 2006.
148 Ibid.
Universitas Indonesia
125
tuntutan penjara atas pelanggaran maupun kejahatan dan
tersangka lain akan dihukum penjara 3 tahun. Namun,
jika dia mengaku dan kamu tidak, maka kamu akan dihukum
penjara 3 tahun dan dia dibebaskan. Jika kalian berdua
mengaku, kami tidak memerlukan kesaksian dari kalian
berdua dan kalian akan dihukum penjara 2 tahun. Jika
tidak ada yang mengaku, maka kalian akan dihukum
penjara 1 tahun atas pelanggaran. Rekanmu juga
diberikan tawaran yang sama.
Bagan I. Bagan Prisoner’s Dilemma dengan bukti pelanggaran
A
B
Tidak mengaku Mengaku
Tidak mengaku (A) 1 tahun - (B)
1 tahun
(A) 3 tahun – (B)
0 tahunMengaku (A) 0 tahun – (B)
3 tahun
(A) 2 tahun – (B)
2 tahun
Berdasarkan bagan ini, setiap tersangka (prisoner)
yang mementingkan diri sendiri akan mengaku. Dari
perspektif prisoner A, jika prisoner B mengaku, maka
prisoner A bisa mengaku (dan dihukum penjara 2 tahun)
atau tidak mengaku (dan dihukum penjara 3 tahun). Dalam
kondisi demikian, prisoner A harus mengaku supaya ia
dihukum penjara dengan jangka waktu lebih pendek.
Sebaliknya, jika prisoner B tidak mengaku, maka
prisoner A bisa tidak mengaku (dan dihukum penjara 1
Universitas Indonesia
126
tahun untuk pelanggaran) atau mengaku dan tidak dihukum
penjara sama sekali. Dalam situasi ini, prisoner A
lebih baik mengaku karena ia tidak akan dihukum penjara
dibandingkan dengan jika A tidak mengaku karena ia akan
dihukum penjara 1 tahun. Oleh karena itu, jika prisoner
B mengaku, prisoner A lebih baik mengaku, dan jika
prisoner B tidak mengaku, lebih baik untuk prisoner A
jika ia mengaku. Skema ini membuat pengakuan menjadi
strategi dominan (dominant strategy) karena prisoner A
akan tetap berada dalam situasi yang lebih terlepas
dari apakah B mengaku atau tidak.149
Kelemahan skema di atas adalah keuntungan untuk
mengaku akan diambil oleh kedua tersangka karena lebih
baik bagi keduanya untuk mengaku daripada tidak
(terlepas dari apakah rekannya mengaku). B juga
diberikan tawaran yang sama dan oleh karenanya
pengakuan merupakan strategi dominannya. Jika setiap
tersangka mengejar keuntungan dominannya dan mengaku,
maka keduanya akan berada dalam posisi yang lebih
buruk daripada yang seharusnya. Ketika kedua tersangka
mengaku, masing-masing akan dihukum penjara 2 tahun.
149 Strategi dominan terwujud jika seorang pemain akan beradadalam kondisi yang lebih baik jika ia memilih opsi tertentuterlepas dari apa yang akan dilakukan oleh rekannya. Sebaliknya,jika seorang pemain bisa berada dalam kondisi yang lebih baik jikaia mengubah pilihannya setelah ia mengetahui pilihan rekannya,maka tidak ada suatu pilihan yang mendominasi pilihan lainnyadalam situasi apapun (apakah rekannya mengaku atau tidak), dantidak ada strategi dominan. Oleh karena itu, tidak terwujudstrategi prisoner’s dilemma.
Universitas Indonesia
127
Namun, jika kedua tersangka saling bekerjasama dan
tidak ada yang mengaku, maka masing-masing tersangka
akan dihukum penjara 1 tahun untuk pelanggaran. Hal ini
menunjukkan bahwa penggunaan strategi dominan oleh
kedua tersangka menghasilkan “hasil Pareto Inferior”150
karena kedua tersangka masih bisa meningkatkan kondisi
mereka jika keduanya berpindah dari skema Mengaku-
Mengaku (dihukum penjara 2 tahun) ke skema Tidak
Mengaku-Tidak Mengaku (dihukum penjara 1 tahun).
Dalam situasi dimana terdapat kekurangan bukti
untuk penuntutan, prisoner’s dilemma adalah senjata
terbaik jaksa penuntut umum. Akan jauh lebih mudah
untuk memenangkan tuntutan jika satu atau lebih anggota
konspirasi (misalnya kartel) telah mengaku, terutama
untuk konspirasi penetapan harga,151 yang sulit untuk
dibuktikan jika tidak ada kesaksian dari salah satu
kartelis. Selain menyediakan/mendapatkan bukti
150 Pareto atau efisiensi pareto atau optimalisasi paretoadalah konsep dalam disiplin ilmu ekonomi yang menyatakan bahwatidak mungkin ada kondisi dimana 1 orang bisa berada dalam kondisiyang lebih baik tanpa membuat kondisi orang lain menjadi lebihburuk. Pareto improvement atau pareto-optimal move atau pareto superiorterjadi jika sejumlah individu diberikan pilihan alokasi barang-barang atau hasil, perubahan dari alokasi (tempat) yang satu kealokasi (tempat) yang lain membuat setidaknya satu individu beradadalam kondisi yang lebih baik tanpa membuat individu lain beradadalam kondisi yang lebih buruk. Dengan kata lain pareto superiorterjadi ketika tidak ada pilihan lain yang lebih baik bagi setiapindividu atau jika tidak ada kemungkinan yang lebih baik bagiindividu manapun. Pareto-inferior terjadi ketika masih ada pilihanlain yang mungkin memosisikan setiap individu dalam kondisi yanglebih baik.
151 Christopher R. Leslie (1), op.cit.
Universitas Indonesia
128
permulaan terjadinya kartel, pihak yang mengaku juga
bisa membantu jaksa penuntut umum untuk menemukan bukti
lain/tambahan untuk membuktikan terjadinya kartel.
Prisoner’s dilemma umumnya adalah model teoritis
permainan yang digunakan untuk menjelaskan sifat/sikap
yang tidak berkaitan dengan jaksa penuntut umum atau
tersangka. Namun, terkait investigasi kartel, bahasa
dari bagan prisoner’s dilemma memetakan kenyataan dari
pertanyaan terkait kartel.152 Jaksa penuntut umum selalu
berupaya untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka
penetapan harga karena pembuktian sangat sulit
dilakukan tanpa pengakuan dan bantuan dari pelaku
pembantu (co-conpirator).
Sayangnya, jaksa penuntut umum, pada kenyataannya,
sering tidak memiliki bukti permulaan (leverage) yang
dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam kerangka model
teoritis di atas. Dalam model prisoner’s dilemma di atas,
jaksa penuntut umum memiliki bukti permulaan yang cukup
untuk memenjarakan kedua tersangka atas pelanggaran.
Fakta ini merupakan faktor yang penting karena kedua
tersangka akan dihukum penjara atas pelanggaranwalaupun
keduanya tidak mengaku melakukan kejahatan. Ketiadaan
bukti atas terjadinya pelanggaran akan menghilangkan
efek prisoner’s dilemma.153
152 Ibid.
153 Ibid.
Universitas Indonesia
129
Bukti untuk pelanggaran sebagai leverage umumnya
merupakan bukti yang terkait dengan penetapan harga.
Misalnya, pelanggaran atas pemalsuan dokumen dengan
sengaja. Dalam kasus penetapan harga lelang rumah di
Amerika Serikat, CEO Sotheby menandatangani surat
kepada editor Sotheby, Deloitte & Touche, yang
menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum oleh
direktur Sotheby.154 Dengan menandatangani surat
tersebut, direktur Sotheby melanggar hukum federal.155
Namun, jaksa penuntut umum tidak bisa menggunakan bukti
ini sebagai leverage atas direktur Sotheby karena bukti
tersebut merupakan bukti turunan (derivative) dari
kejahatan hukum persaingan usaha. Tanda tangan Direktur
Sotheby merupakan kejahatan hanya karena adanya
konspirasi penetapan harga. Dengan kata lain, jaksa
penuntut umum masih harus membuktikan kejahatan hukum
persaingan usaha untuk membuktikan pelanggaran (minor
crime) atas pemalsuan dokumen oleh Direktur Sotheby.
Dalam konteks konspirasi penetapan harga, ketiadaan
bukti pelanggaran berarti korporasi secara rasional
akan menentukan bahwa lebih menguntungkan untuk
melanjutkan kartel daripada membongkarnya. Melanjutkan
kartel merupakan sumber pundi uang yang berlimpah ruah
dan ini adalah alasan mengapa korporasi tersebut
menjadi anggota kartel awalnya. Mengakui pertama154 Christopher Mason, The Art of the Steal, 199 (2004) seperti
dikutip dalam ibid.
155 Ibid.
Universitas Indonesia
130
berarti tidak ada hukuman penjara untuk para eksekutif
yang terlibat dalam penetapan harga. Namun, selama
kartel itu stabil dan tidak terdeteksi, tidak ada orang
yang masuk penjara. Tidak hukuman penjara ditambah
keuntungan kartel adalah jauh lebih menguntungkan
daripada tidak ada hukuman penjara tanpa keuntungan
kartel. Jika tidak ada anggota kartel yang mengaku dan
kartel kelihatan stabil, maka prinsip rationally self-interest
tidak akan menyebabkan pengkhianatan (defection) anggota
kartel.
Bagan II. Bagan Prisoner’s Dilemma tanpa leverage (bukti permulaan atas
pelanggaran)
A
B
Tidak mengaku Mengaku
Tidak mengaku (A) 0 tahun - (B)
0 tahun
(A) 3 tahun – (B)
0 tahunMengaku (A) 0 tahun – (B)
3 tahun
(A) 2 tahun – (B)
2 tahun
Bagan di atas menunjukkan ketiadaan strategi dominan.
Hasil terburuk yaitu 3 tahun penjara, muncul jika
seorang tersangka menolak untuk bekerjasama dengan
jaksa penuntut umum ketika rekan kerjanya telah
mengaku. Oleh karena itu, setiap tersangka tersebut
lebih baik mengaku jika rekan kerjanya telah mengaku.
Namun, jika rekan kerjanya tidak mengaku, maka
Universitas Indonesia
131
tersangka tersebut tidak dihukum penjara sama sekali.
Hal ini merupakan kelemahan dari Corporate Leniency Program
1993 Amerika Serikat. Bagan di atas tidak menentukan
apakah seorang tersangka lebih diuntungkan dengan
mengaku atau tidak mengaku ketika rekan kerjanya diam
(tidak mengaku).156 Dalam kondisi ini, tersangka
tersebut hanya akan mendapatkan insentif yang kecil
dari pengakuannya. Dengan kata lain, karena pihak A
mengetahui bahwa B tidak eligible untuk program amnesti
(karena B adalah ring leader),157 maka A akan cenderung
untuk tidak mengaku karena ia lebih yakin bahwa B tidak
akan mengakui adanya kartel.
Namun, bagan ini mengeyampingkan tingkat
kompleksitas yang sebenarnya dari dilema kartelis untuk
mengaku atau tidak. Dalam kenyataannya, pembuat
keputusan bisnis tidak hanya mempertimbangkan sanksi
pidana penjara dalam memutuskan akan bergabung dengan
kartel atau tidak.158 Pelaku usaha menghendaki
keuntungan maksimal dengan meminimalisasi resiko
dihukum penjara. Oleh karena itu, matriks prisoner’s
156 Dalam kenyataannya, suatu pengakuan akan menjadi strategidominan yang lemah karena jika ada resiko salah seorang rekankerjanya mengaku, maka ia juga harus mengaku.
157 Syarat untuk mendapatkan amnesti berdasarkan CorporateLeniency Program tahun 1993 adalah, salah satunya, pelaku usahatersebut merupakan pemimpin atau inisiator kartel.
158 Jika korporasi hanya mempertimbangkan faktor resiko sanksipidana penjara, maka tidak akan ada pembuangan limbah sembarangandan penipuan.
Universitas Indonesia
132
dilemma harus menyertakan dua variabel yang berbeda,
lama hukuman penjara dan jumlah uang. Jika uang
diikutsertakan dalam faktor pertimbangan para pelaku
usaha untuk melakukan kartel, maka pengakuan bersalah
kelihatan jauh lebih merugikan (menarik).
Terdapat beberapa kerugian bagi pelaku usaha untuk
menguak partisipasinya dalam kartel penetapan harga.159
Pertama, pelaku usaha pada umumnya bergabung dengan
kartel untuk memaksimalkan keuntungan. Penetapan harga
bisa memberikan keuntungan ratusan juga dolar bagi
pelaku usaha, tergantung pada produk pasar yang
dimaksud.160 Pengakuan juga menghancurkan kartel yang
sudah ada dan menghilangkan kesempatan bagi pelaku
usaha tersebut untuk bergabung dengan kartel lainnya di
masa yang akan datang karena pelaku usaha yang menguak
suatu kartel tidak akan pernah dipercayai lagi oleh
pelaku usaha lain untuk mengadakan kartel di masa yang
akan datang, bahkan untuk produk pasar yang berbeda.161
Oleh karena itu, keputusan untuk mengaku bisa
mengakibatkan kerugian jutaan dolar bagi kartel yang
sudah ada. Hilangnya potensi keuntungan dari kartel
yang sudah ada maupun kartel di masa yang akan datang
ini dinamakan opportunity cost.159 Christopher R. Leslie (1), op.cit.
160 Robert H. Lande, Why Antitrust Damage Levels Should Be Raised, 16Loy. Consumer L. Rev. 329 (2004) seperti dikutip oleh ChristopherR. Leslie, Ibid.
161 Christopher R. Leslie (2), Trust, Distrust, and Antitrust, 82 TexasLaw Review, 643-45 (2004).
Universitas Indonesia
133
Kedua, selain opportunity cost, pengakuan juga akan
menguak keikutsertaan anggota kartel lainnya terhadap
gugatan perdata antitrust. Untuk lebih dari satu abad,
semua penggugat yang berhasil dalam gugatan perdata
berdasarkan Sherman Act berhak atas ganti rugi tiga kali
lipat (atau treble damages). Treble damages ini merupakan
insentif yang sangat besar bagi pelaku usaha untuk
tidak melanggar hukum persaingan usaha, atau setidaknya
untuk tidak tertangkap. Treble damages juga menjadi
alasan bagi pelaku usaha untuk tidak mengaku sama
sekali atau tidak mendekati penyidik kasus persaingan
usaha sebelum investigasi dilakukan atau sebelum ada
tekanan luar untuk mengaku. The Antitrust Criminal Penalty
Enhancement and Reform Act 2004 menghapus/membatalkan
aturan tentang treble damages bagi pelaku usaha yang
mengaku pertama atas keikutsertaannya dalam konspirasi
kartel penetapan harga tertentu. Walaupun hal ini
mengurangi disincentive marginal untuk mendapatkan amnesti,
pengakuan masih merupakan pengakuan kesalahan dan
akibatnya pertanggungjawaban. Dengan adanya pengakuan
kesalahan, maka individu yang merasa dirugikan oleh
kartel tersebut tidak perlu lagi membuktikan adanya
kartel, melainkan hanya membuktikan jumlah kerugian
yang mereka derita. Ganti rugi tunggal (single damage)
bisa saja mencapai ratusan juta dolar.
Ketiga, pengakuan keterlibatan dalam kartel
penetapan harga mempunyai implikasi yang lebih jauh
Universitas Indonesia
134
daripada hanya sekedar hukum persaingan usaha. Ketika
pelaku usaha mengaku telah melanggar hukum persaingan
usaha, pada saat bersamaan pelaku usaha tersebut juga
bisa dijerat dengan pelanggaran hukum lainnya (selain
hukum persaingan usaha) karena semua dokumen yang
bersifat rahasia (confidential) akan terkuak. Misalnya,
penggelapan dan pemalsuan surat.
Keempat, pengakuan keterlibatan dalam kartel
penetapan harga juga mengekpos pelaku usaha tersebut
kepada gugatan ganti rugi atau investigasi otoritas
persaingan usaha di negara lain. Misalnya, Uni Eropa
menjatuhkan hukum ganti rugi sebesar USD 150.4 juta
kepada pelaku usaha yang terlibat dalam kartel lysine,
USD 132 juta kepada pelaku usaha yang terlibat dalam
kartel kotak karton, dan USD 248 juta kepada anggota
kartel penetapan harga semen.162
Kelima, kerugian (disinsentif) lain yang dialami
anggota kartel yang mengaku adalah (i) kehilangan
waktu, sumber daya, dan energi yang harus dialihkan
untuk membantu otoritas persaingan usaha dan untuk
mengajukan pembelaan atas gugatan perdata, (ii) resiko
kehilangan pekerja, pejabat perusahaan, atau ahli-ahli
perusahaan yang tidak ingin lagi bekerja di perusahaan
yang tersandung kasus persaingan usaha, dan (iii)
hancurnya reputasi mereka.
162 Donald I. Baker, The Use of Criminal Law Remedies to Deter and PunishCartels and Bid-Rigging, 69 Georgetown Washington Law Review. 693, 701(2001) seperti dikutip Christopher R. Leslie (1), op.cit.
Universitas Indonesia
135
Tidak seperti halnya bos mafia yang anggota
keluarga dan kroninya mungkin sudah diketahui atau
diduga oleh banyak orang terlibat dalam bisnis kotor,
kebanyakan pelanggar hukum persaingan usaha adalah
anggota masyarakat yang dianggap (kelihatannya)
mematuhi hukum. Mengakui kesalahan (kejahatan)
mengundang caci-maki dari masyarakat umum dan
menyebabkan rasa malu.
Ketika faktor-faktor yang dijelaskan di atas
diikutsertakan (dimasukkan sebagai variabel baru) yang
mana tidak terkait dengan hukuman langsung atas
pelanggaran hukum persaingan usaha, maka kelihatan
jelas bahwa pengakuan bukan merupakan strategi dominan.
Bagan III di bawah menunjukkan preferensi bagi anggota
kartel dalam situasi dimana setiap pelaku usaha
mempertimbangkan biaya total untuk mengaku. Bagan
tingkat preferensi mencerminkan fakta bahwa setiap
anggota kartel tidak hanya ingin menghindari hukuman
penjara; mereka ingin menghindari hukuman penjara dan
pada saat yang sama memaksimalkan keuntungannya.
Keuntungan dimaksimalkan dengan mendapatkan keuntungan
kartel dan pada waktu yang sama menghindari hukum
penjara dan gugatan ganti rugi tiga kali lipat (treble
damages).
Bagan III. Tabel Preferensi jika Penuntut Umum tidak mempunyai
bukti pelanggaran (tidak ada leverage)
Universitas Indonesia
136
A
B
Tidak mengaku Mengaku
Tidak mengaku (A) 1 tahun - (B)
1 tahun
(A) 4 tahun – (B)
2 tahunMengaku (A) 2 tahun – (B)
4 tahun
(A) 3 tahun – (B)
3 tahun
Bagan di atas menggambarkan dengan lebih jelas
ketiadaan strategi dominan. Hasil akhir terburuk akan
dialami pelaku usaha jika ia tidak mengaku padahal
rekan kerjanya mengaku. Strategi ini akan menghasilkan
hukuman penjara maksimal, menghancurkan kartel,
menghentikan pengalihan surplus konsumen kepada
produsen, menguak kartel dan mengekpsos pelaku usaha
kepada gugatan ganti rugi perdata, tanggung jawab atas
pelanggaran hukum persaingan usaha di negara lain,
menguak potensi pelanggaran hukum lain, dan
menghancurkan reputasi pelaku usaha tersebut. Namun,
hasil terbaik bagi pelaku usaha adalah sama-sama tidak
mengaku. Jika rekan usahanya belum mengaku, maka lebih
baik untuk pelaku usaha tersebut untuk tidak mengaku.
Walaupun pelaku usaha yang mengaku mendapatkan amnesti,
pengakuan tersebut akan menghancurkan kartel dan
mengekspos pengaku terhadap berbagai gugatan ganti rugi
perdata dan kerugian lain. Dengan kata lain, selama
rekan usahanya belum mengaku, maka pelaku usaha
tersebut akan merasa yakin bahwa ia tidak akan
Universitas Indonesia
137
tertangkap dan dihukum penjara. Lebih baik tidak
dihukum penjara dan pada saat yang sama mendapatkan
keuntungan kartel (yaitu dengan tidak mengaku) daripada
menghindari hukuman penjara namun pada saat yang sama
menderita kerugian akibat gugatan ganti rugi perdata
(yaitu dengan mengaku). Dalam kondisi ini, setiap
pelaku usaha lebih baik menunggu gerak-gerik rekan
kerjanya dan meniru respons rekan kerjanya terhadap
tawaran dari otoritas persaingan usaha. Hal ini
dinamakan coordination game.163 Hal ini juga berarti tidak
ada pelaku usaha yang mempunyai strategi dominan. Oleh
karena itu, pengakuan bukan merupakan strategi dominan.
Otoritas persaingan usaha harus mencari cara untuk
memanipulasi insentif pelaku usaha untuk menciptakan
prisoner’s dilemma dimana pengakuan merupakan strategi
dominan.
4.2. Cara Merumuskan Kebijakan Sanksi Terhadap Kartel
Untuk Meningkatkan Efek Jera di Amerika Serikat
Pada bagian ini, Penulis akan memaparkan secara
rinci pertimbangan dan dilema yang dihadapi Amerika
Serikat dalam menentukan sanksi pidana penjara, sanksi
pidana denda, dan gugatan ganti rugi perdata.
Pertimbangan semacam ini bisa menjadi masukan (atau
163 Tom Ginsburg & Richard H. McAdams, Adjudicating in Anarchy: AnExpressive Theory of International Dispute Resolution, 45 Wm. & Mary LawReview. 1229, 1245-49 (2004) seperti dikutip Christopher R. Leslie(1), op.cit.
Universitas Indonesia
138
kritik konstruktif) bagi legislator Indonesia dalam
menyempurnakan kajian tentang dasar kriminalisasi
kartel dan penentuan sanksi kartel.
4.2.1 Gambaran umum tentang Teori Efek Jera Kartel
(Cartel Deterrence)
Cara yang efektif untuk menganalisis apakah suatu
sistem berhasil mencapai tujuannya adalah dengan
melihat apa keputusan yang akan diambil oleh suatu
pelaku usaha yang dihadapkan dengan pilihan tertentu.164
Daniel Fletcher menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga)
faktor utama yang mempengaruhi keputusan pelaku usaha
untuk bergabung dengan suatu kartel, yaitu: (1) tingkat
kemungkinan (baca: probabilitas) untuk mendeteksi dan
menghukum pelaku kartel (p), (2) hukuman, termasuk
sanksi pidana denda dan sanksi pidana penjara (F), dan
(3) keuntungan tambahan yang diharapkan oleh pelaku
usaha jika pelaku usaha tersebut bergabung dengan
kartel (Ep).165 Jika jumlah/tingkat hukuman (pF) adalah
164 Daniel J. Fletcher, The Lure of Leniency: Maximizing Cartel Deterrencein Light of La Roche V. Empagran and the Antitrust Criminal Penalty Enhancement andReform Act of 2004, Transnational Law and Contemporary Problems,University of Iowa College of Law, 2005, 15 Transnat'l L. &Contemp. Probs. 341.
165 Lihat Brief for Economists Joseph E. Stiglitz dan Peter R. Orszag sebagai
Amicus Curiae Supporting Respondents dalam kasus F. Hoffman-Laroche, Ltd.v. Empagran, 124 S.Ct. 2349 (2004) (No. 03-724) seperti yangdikutip Daniel J. Fletcher, Id. Falsafah konstitusional HukumAntitrust Amerika Serikat adalah bahwa kartel merupakan kejahatan(evil) ekonomi yang fundamental yang harus dihentikan atau dicegaholeh pemerintah federal Amerika Serikat.
Universitas Indonesia
139
lebih besar dari keuntungan tambahan yang diharapkan
oleh pelaku usaha untuk bergabung dengan kartel (Ep),
maka pelaku usaha yang rasional tidak akan bergabung
dengan kartel.166 Ide ini bisa disimpulkan dengan
operasi matematika yang sederhana, yaitu:167
Otoritas persaingan usaha berupaya meningkatkan
level p dan F untuk memaksimalisasi efek jera dari
kartel. Karena dengan kombinasi p dan F, maka
kemungkinan pF akan lebih besar daripada Ep akan
meningkat (20)168
4.2.2 Teori Efek Jera Kartel Awal di Amerika
Serikat (Sebelum Program Corporate Leniency 1993)
Pada umumnya, diasumsikan bahwa peningkatan p atau
F akan meningkatkan efek jera.169 Lebih lanjut, Antitrust
Division seharusnya berupaya meningkatkan p atau F. Tiga
hukuman yang berbeda berikut dikombinasikan untuk
membentuk F, yaitu: (1) sanksi pidana penjara, (2)166 Christopher R. Leslie (2), op.cit.
167 Brief for Economists Joseph E. Stiglizts dan Peter R. Orszag, op.cit.
168 Scott D. Hammond (2) op.cit. Jika pelaku usaha mengetahuibahwa resiko “ditangkap” atau “ketahuan” oleh otoritas persainganusaha sangat kecil, maka sanksi pidana denda maksimum yang kakutidak akan cukup untuk menciptakan efek jera terhadap aktivitaskartel.
169 Pfizer, Inc. v. Gov't of India, 434 U.S. 308 (1978),seperti dikutip oleh Daniel J. Fletcher, op.cit.
Universitas Indonesia
jika pF>Ep, maka tidak ada kartel
140
ganti rugi perdata, dan (3) sanksi pidana penjara.170
Sebelum disahkannya Corporate Leniency Policy, p
ditentukan/dipengaruhi oleh kemampuan Antitrust Division
untuk mendeteksi kartel melalui teknik memata-matai
(spying) seperti surat perintah penggeledahan (search
warrants), rekaman suara atau gambar rahasia (secret audio
or videotapes), dan interogasi Federal Bureau Investigation
(FBI).171 Alasan peningkatan baik p maupun F akan
meningkatkan efek jera adalah karena p dan F adalah dua
variabel yang independen satu sama lain. Peningkatan
atau pengurangan F tidak mempunyai pengaruh pada
peningkatan/pengurangan p. Contohnya, bahkan dalam
peningkatan sanksi denda perdata, jumlah kartel yang
dideteksi tidak berubah (tetap sama jumlahnya).
Alasan (rationale) ini dijelaskan oleh Mahkamah Agung
Amerika Serikat melalui pertimbangannya dalam kasus
Pfizer, Inc v. Government of India.172 Dalam kasus tersebut,
Mahkamah Agung memutuskan bahwa negara asing (baik
individu, korporasi maupun entitas lainnya) bisa
menggugat (perdata) kerugian akibat pelanggaran hukum
persaingan usaha dengan treble damages terhadap korporasi
Amerika Serikat di pengadilan Amerika Serikat.173
170 Kartel merupakan pelanggaran per se berdasarkan Section 1Sherman Act.
171 Scott Hammond (2), op.cit.
172 Ibid.
173 Pfizer, Inc. v. Gov't of India, 434 U.S. 308 (1978),seperti dikutip oleh Daniel J. Fletcher, op.cit.
Universitas Indonesia
141
Mahkamah Agung Amerika Serikat berargumen bahwa jika
negara asing tidak diizinkan untuk menggugat ganti rugi
(perdata) di pengadilan Amerika Serikat,174 maka efek
jera kartel akan terhambat/berkurang, karena jika
gugatan ganti rugi (perdata) diizinkan,175 maka F akan
meningkat pesat dan oleh karena itu akan meningkatkan
efek jera kartel.
Secara umum, alasan (reasoning) di atas merupakan
pandangan umum sebelum munculnya dampak dari Corporate
Leniency Program.176 Namun, sejak Department of Justice Amerika
Serikat memperkenalkan Corporate Leniency Program, reasoning
ini mulai dipertanyakan.
4.2.3 Dampak Corporate Leniency Program 1993 Amerika
Serikat dalam mengurangi kartel (Efek Jera
Kartel).
Untuk mengatasi kesulitan mendeteksi kartel,177
pemerintah Amerika Serikat mengimplementasikan Corporate
174 Ibid.
175 Ibid
176 Perlu dicatat bahwa corporate leniency program awalnyadiperkenalkan pada tahun 1978 yaitu pada tahun yang samaPengadilan menghukum Pfizer, Namun, corporate leniency program belumbegitu efektif sebelum tahun 1993 ketika Kongres Amerika Serikatmemasukkan elemen kunci dalam corporate leniency program yang baru.
177 Brief for Economists Joseph E. Stiglizts dan Peter R. Orszag, op.cit.menyatakan “konspirasi penetapan harga termasuk pelaku usaha yangberoperasi secara global, dan secara alami merupakan kejahatanyang sangat sulit dideteksi dan dihukum.”
Universitas Indonesia
142
Leniency Program pada tahun 1993. Program ini mempunyai
tujuan untuk mengurangi pembentukkan kartel dengan
mendeteksi dan menghukum kartel yang sudah ada. Dalam
operasi matematika seperti yang digambarkan di atas,
Corporate Leniency Program berupaya meningkatkan p dengan
mendeteksi lebih banyak kartel, dan oleh karenanya
meningkatkan efek jera.
Seperti yang telah dijelaskan di atas, kunci utama
Corporate Leniency Program 1993 yang juga ditegaskan dalam
kasus LaRoche v. Empagran,178 adalah bahwa pelaku usaha
yang masuk dalam program tersebut tidak diberikan
amnesti (dibebaskan) dari gugatan ganti rugi perdata.179
Oleh karena itu, jika anggota kartel mengaku bersalah
sebagai syarat untuk mendapatkan amnesti, pelaku usaha
tersebut tetap harus membayar ganti rugi treble damages.
Seperti yang telah dijelaskan di atas (pF>Ep),
kemungkinan untuk mendeteksi kartel adalah faktor utama
(kunci) untuk meningkatkan efek jera. Corporate Leniency
Program 1993 berupaya untuk meningkatkan probabilitas
(kemungkinan) mendeteksi kartel dengan mendorong
anggota kartel untuk melaporkan (mengaku bersalah).
Oleh karena itu, dampak Corporate Leniency Program 1993
terhadap efek jera adalah fungsi langsung/utama dari178 Hoffman-Laroche, Ltd. v. Empagran, 124 Supreme Court 2359, 2363
(2004).
179 Kongres mengesahkan amandemen penting pada tahun 2004 yangmemberikan keringanan bagi pelaku usaha yang mengaku bersalahdengan memberikan amnesti (memaafkan) gugatan ganti rugi perdatatreble damages.
Universitas Indonesia
143
kemampuan Corporate Leniency Program 1993 untuk mendorong
pelaku usaha untuk mengaku bersalah.
Setiap anggota kartel mempunyai pilihan untuk
bergabung atau tidak bergabung dengan kartel. Asumsikan
jika pelaku usaha hanya berupaya untuk memaksimalisasi
keuntungan, maka pelaku usaha tersebut akan tetap
bergabung dengan kartel jika tindakan tersebut akan
memaksimalisasi keuntungan. Keputusan ini terlihat
jelas dalam operasi matematika yang baru.180
Pertama, variabel dalam operasi matematikanya
adalah sebagai berikut:
EpLeniency = keuntungan yangdiharapkan pelaku usaha jika iamengaku bersalah (mendapatkan amnesti)
NCEstimated Profits = Jumlah keuntungan yangdiharapkan jika pelaku usaha tidakbergabung dalam kartel
CiF = Ganti rugi perdata
EpNo Leniency = Keuntungan yang diharapkan jikapelaku usaha tidakmengaku bersalah (mendapatkankeringanan/amnesti)
CEstimated Profits = Keuntungan yang diharapkanjika pelaku usaha bergabungdengan kartel
180 Pernyataan ini mirip dengan pendapat Bruce H. Kobayashi,Antitrust, Agency, and Amnesty: An Economic Analysis of the Criminal Enforcement of theAntirust Laws Against Corporations, 69 George Washington Law Review. 715(2001), seperti yang dikutip dalam Daniel J. Fletcher, op.cit.
Universitas Indonesia
144
P = Kemungkinan (probabilitas) mendeteksi
kartel
CrF = Sanksi pidana denda
CrS = Sanksi pidana penjara
Bagan operasi matematika kartel 181
Operasi matematika Corporate Leniency Program adalah:
Maka pelaku usaha yang rasional akan mengaku bersalah
(menerima amnesti). Jika jumlah pelaku usaha yang
mengaku bersalah, p dalam pF>Ep182 meningkat dan oleh
karenanya adanya peningkatan efek jera.
4.2.3.1 Kunci observasi pertama: dua ciri utama dari
Corporate Leniency Program 1993181 Daniel J. Fletcher, op.cit.
182 Gary R. Spratling, Making Companies an Offer They Shouldn't Refuse:The Antitrust Division's Corporate Leniency Policy--An Update, disampaikan padaat The Bar Association of the District of Columbia's 35th Annual Symposium onAssociations and Antitrust (Feb. 16, 1999). Kunjungi at http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/2247.htm (kunjungan terakhir 6Mei 2010).
Universitas Indonesia
Bagan 1: EpLeniency = NCEstimated Profits - CiF
Bagan 2: EpNoLeniency = CEstimated Profits
Jika NCEstimated Profits - CiF > CEstimated Profits(1- p) -
p(CiF + CrF + CrS)
145
Operasi matematika di atas menciptakan dua ciri
utama.183 Pertama, operasi matematika tersebut
menciptakan insentif langsung bagi pelaku usaha untuk
mengaku bersalah karena terdapatnya janji amnesti
sanksi pidana penjara. Kedua, operasi matematika
tersebut menciptakan perasaan saling tidak percaya
diantara pelaku usaha karena setiap pelaku usaha
mengetahui bahwa pelaku usaha lain dalam suatu kartel
mempunyai insentif langsung yang sama untuk menghindari
sanksi pidana penjara.184 Ciri kedua ini menciptakan
insentif yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk
mengaku bersalah. Kedua ciri operasi matematika di atas
yang saling terkait menciptakan situasi dimana akan
jauh lebih baik bagi pelaku usaha yang terlibat kartel
untuk mengaku bersalah.
Ide ini dikembangkan dan dijelaskan dengan sangat
rinci oleh Christopher R. Leslie melalui skema strategi
prisoner’s dilemma185 yang menyatakan bahwa tanpa adanya
ketidakpercayaan dari awal (yaitu mengetahui bahwa
anggota kartel lainnya juga ingin menghindari sanksi
183 Daniel J. Fletcher, op.cit.
184 Christopher R. Leslie (2), op.cit., seperti dikutip dalamDaniel J. Fletcher, op.cit. “Secara singkat, Corporate Leniency Programmempunyai dua efek: menyediakan insentif langsung untuk mengakubersalah dan menciptakan ketidakpercayaan diantara sesama anggotakartel yang malah menjadi insentif tambahan untuk mengaku.”
185 Christopher R. Leslie (2), op.cit.
Universitas Indonesia
146
pidana penjara), pelaku usaha tidak mendapatkan
insentif yang cukup untuk mengaku bersalah.
Ide Christopher R. Leslie menjadi lebih jelas jika
disandingkan dengan operasi matematika di atas.186
Asumsikan 100% dari seluruh kartel yang terdeteksi
melalui corporate leniency program, jika pelaku usaha
mempercayai satu sama lain, maka tidak ada pelaku usaha
yang mengaku bersalah dan p = 0.187 Bagian kanan dari
operasi matematika akan secara substansial menjadi
lebih besar daripada bagian kiri. Hal ini menunjukkan
bahwa setiap pelaku usaha akan lebih memilih bergabung
dengan kartel karena keuntungannya lebih besar. Namun,
menurut Christopher R. Leslie dengan teori strategi
prisoner’s dilemma, hal di atas tidak akan terjadi karena
pelaku usaha akan lebih memilih untuk mengaku bersalah.
Seperti yang telah dijelaskan di atas (Lihat Bagian
4.1 B Skripsi ini), model prisoner’s dilemma menunjukkan
mengapa corporate leniency program 1993 menciptakan, pada
mulanya, rasa saling tidak percaya diantara anggota
kartel. Singkatnya, setiap anggota kartel akan
bertindak secara rasional demi kepentingan diri sendiri
karena jika anggota kartel tersebut tidak mengaku dan
rekan kerjanya (anggota kartel lain) maka hukuman yang
dijatuhkan kepada anggota kartel tersebut adalah yang
186 Daniel J. Fletcher, op.cit.
187 Dengan asumsi tidak ada faktor lain yang mungkinmenghancurkan kartel.
Universitas Indonesia
147
paling tinggi sehingga pilihan terbaik adalah mengaku
bersalah. Fenomena ini disebut juga “race to the
courthouse”.188 Jurnalis Janet Novack menyatakan urgensi
pelaku usaha untuk mengaku bersalah duluan daripada
pelaku usaha lain untuk mendapatkan amnesti sebagai
berikut.189
"If someone in your company has been conspiring with competitors
to fix prices here's some sound advice. Get to the Justice Department
before your co-conspirators do. Confess and the United States Department
of Justice will let you off the hook. But hurry! Only one conspirator per
cartel."
Terjemahan bebasnya:
“Jika seseorang di perusahaan anda terlibat dalam
konspirasi dengan pelaku usaha pesaing anda untuk
menetapkan harga, ada saran untuk anda. Segeralah pergi
ke Justice Departement sebelum pelaku usaha pesaing/lain
melakukannya. Mengakulah dan Justice Department akan
melepaskan anda dari tuntutan. Namun bergegaslah! Hanya
tersedia satu amnesti untuk satu kartel.”
Singkatnya, Corporate Leniency Program 1993
meningkatkan jumlah kartel yang terdeteksi karena rasa
takut bahwa anggota kartel lainnya akan mengaku duluan,
sehingga menciptakan insentif untuk mengaku duluan.
Kondisi ini membuat kartel lebih labil sehingga pelaku188 Scott D. Hammond (2), op.cit. “Sistem pendekatan “winner-take-
all” mendorong terjadinya persaingan diantara anggota kartelsehingga terjadi ketegangan dan ketidakpercayaan diantara anggotakartel.”
189 Gary R. Spratling, op.cit.
Universitas Indonesia
148
usaha independen (yang bukan anggota kartel) lebih
terdorong untuk tidak bergabung dengan kartel. Oleh
karena itu, dengan meningkatkan kemampuan mendeteksi
kartel, Corporate Leniency Program 1993 meningkatkan efek
jera kartel.
4.2.3.2 Kunci observasi kedua: Interdependensi p dan
F
Corporate Leniency Program 1993 telah mengubah teori
efek jera kartel karena peningkatan dalam satu variabel
(p atau F) bisa menyebabkan penurunan dalam variabel
lain. Dengan kata lain, jika hukuman (F) ditingkatkan
secara signifikan, maka hukuman tersebut mengurangi
probabilitas Antitrust Division untuk mendeteksi kartel
(p). Alasannya adalah karena Corporate Leniency Program
1993 tidak memberikan amnesti kepada anggota kartel
untuk gugatan ganti rugi perdata. Jika pelaku usaha
menghadapi gugatan ganti rugi perdata yang besar, ia
otomatis harus membayar ganti rugi tersebut jika ia
mengaku. Namun kemungkinan dihukumnya pelaku usaha
tersebut untuk membayar ganti rugi sangat kecil jika ia
tidak mengaku. Prinsipnya adalah hidup dengan
‘kemungkinan’ dihukum penjara mungkin merupakan pilihan
yang lebih baik daripada ‘dipastikan’ harus membayar
ganti rugi perdata yang besar. Oleh karena itu, F yang
besar mungkin akan menurunkan pelaku usaha yang mengaku
bersalah dan pada gilirannya menurunkan p.
Universitas Indonesia
149
Hal di atas menjadi lebih jelas dengan
memperhatikan operasi matematika: jika NCEstimated Profits -
CiF > CEstimated Profits(1- p) - p(CiF + CrF + CrS), maka
pelaku usaha akan memilih untuk mengaku bersalah. CiF
(ganti rugi perdata) adalah sama di dua sisi pada
operasi matematika di atas, tetapi pada bagian kanan
operasi matematika tersebut (tidak ada
leniency/keringanan) CiF dikurangi oleh p. Oleh karena
itu, jika CiF besar, maka mungkin bagian kanan
(keuntungan yang didapatkan jika tidak ada
leniency/keringanan) lebih besar daripada bagian kiri
(keuntungan yang diharapkan jika ada leniency/keringanan)
operasi matematika tersebut. Kondisi ini mengurangi p
dan oleh karenanya mengurangi efek jera.
Kesimpulan di atas bertentangan dengan reasoning
yang dipakai dalam kasus Pfizer. Dalam kasus Pfizer,
Pengadilan mengizinkan negara asing (orang-
perseorangan, badan hukum, atau entitas lainnya) untuk
menggugat korporasi Amerika Serikat atas ganti rugi
perdata, karena menurut Pengadilan peningkatan ganti
rugi perdata akan meningkatkan F dan oleh karenanya
meningkatkan efek jera. Dengan kebijakan baru Corporate
Leniency Program 1993, maka peningkatan ganti rugi
perdata yang besar juga menyebabkan F meningkat, tetapi
akan menurunkan p secara dramatis. Peningkatan salah
satu diantara p atau F tidak lagi meningkatkan efek
Universitas Indonesia
150
jera karena kedua variabel tersebut (p dan F) tidak
lagi interdependen/terkait satu sama lain.
4.3. Kemungkinan penerapan strategi prisoner’s dilemma di
Indonesia untuk menghancurkan kartel dan
meningkatkan efek jera sanksi atas kartel
Pada dasarnya, UU No.5/1999 menetapkan 3 (tiga)
jenis sanksi atas kartel, yaitu sanksi denda
administrasi (Pasal 47 ayat (2) f), ganti rugi perdata
(Pasal 47 ayat (2) g), dan sanksi pidana denda (Pasal
11 juncto 48 ayat (1). Manfaat dari penerapan strategi
prisoner’s dilemma dalam kasus kartel adalah untuk
menentukan jenis sanksi dan meningkatkan efek jera dari
sanksi atas kartel. Seperti yang dijelaskan di bagian
sebelumnya, penentuan sanksi atas kartel baik menurut
UU No.5/1999 maupun KPPU belum jelas.
Menurut Penulis, untuk menerapkan strategi prisoner’s
dilemma, harus dilakukan amandemen terhadap UU No.5/1999
terkait perumusan cara penanganan kejahatan kartel.
Secara konseptual, hal penting yang harus dimasukkan
dalam UU No.5/1999, diantaranya adalah: (i) ketentuan
tentang amnesti bagi pelaku usaha pertama yang mengaku
terlibat dalam kartel dan membantu KPPU dalam proses
investigasi kartel yaitu dengan tidak dituntutnya
pelaku kartel atas pertanggungjawaban pidana, (ii)
ketentuan yang menyatakan bahwa pengakuan keterlibatan
kartel secara otomatis membuktikan kesalahan pelaku
Universitas Indonesia
151
kartel sehingga pihak yang merasa dirugikan secara
perdata (misalnya konsumen) tidak perlu unsur
kesalahan/melawan hukum di pengadilan perdata, (iii)
ketentuan tentang fleksibilitas penjatuhan hukuman oleh
KPPU baik sanksi denda pidana, ganti rugi perdata,
maupun sanksi pidana penjara, (iv) pencabutan sanksi
denda administrasi, dan (v) ketentuan tentang besaran
denda pidana, ganti rugi perdata, maupun sanksi pidana
penjara yang mempertimbangkan faktor tingkat efek jera
dari masing-masing sanksi.
Terkait poin (i), UU No.5/1999 harus mengizinkan
adanya plea bargain dimana pelaku usaha yang mengaku
terlibat dalam kartel serta membantu KPPU dalam proses
investigasi kartel akan diberikan amnesti. Amnesti ini
menciptakan insentif bagi pelaku kartel untuk mengaku
bersalah dan membantu KPPU dalam menginvestigasi dan
membuktikan kejahatan kartel. Berhubung kesuksesan
kartel sangat bergantung pada kepercayaan diantara para
anggotanya, maka insentif amnesti mampu menciptakan
ketidakpercayaan (distrust) dalam suatu kartel, sehingga
kartel tersebut akan hancur. Pelaku kartel pada
dasarnya merupakan makhluk ekonomi yang mengejar
keuntungan. Jika ketentuan persaingan usaha mampu
menciptakan insentif melalui amnesti bagi pelaku usaha
untuk mengaku bersalah dan membantu KPPU dalam proses
investigasi kartel, maka pelaku kartel yang merupakan
Universitas Indonesia
152
mahkluk ekonomi akan mengejar keuntungan dari amnesti
tersebut.
Terkait poin (ii), agar hak “korban” kartel (yaitu
konsumen dan pelaku usaha pesaing aktual dan potensial
dalam pasar yang dikuasai kartel) tetap terlindungi,
maka amnesti yang diberikan kepada pelaku kartel yang
mengaku tidak boleh meliputi amnesti atas ganti rugi.
Alasannya adalah karena hak atas ganti rugi ini
merupakan hak perdata “korban” kartel. Namun, pada saat
yang sama harus dipertimbangkan apakah penentuan ganti
rugi perdata tersebut disesuaikan dengan prinsip KUHPer
yaitu kerugian aktual (biaya, bunga, dan rugi) atau
ditetapkan dengan faktor perkalian tertentu (misalnya
dua kali lipat dari kerugian aktual). Di Amerika
Serikat, perhitungan ini bergantung pada reaksi pelaku
kartel atas ganti rugi yang harus dibayarkannya (lihat
penjelasan butir 4.2.3 Skripsi ini). Jika perhitungan
tersebut menyimpulkan bahwa insentif maksimum tercipta
ketika ganti rugi dihitung berdasarkan kerugian aktual,
maka perhitungan ganti rugi sebaiknya hanya berdasarkan
kerugian faktual.
Terkait poin (iii), seperti yang telah dijabarkan
dalam bagian sebelumnya, kewenangan otoritas persaingan
usaha yang fleksibel (adaptif) dalam menentukan sanksi
yang dijatuhkan penting untuk meningkatkan efek jera
dari sanksi atas kartel. Alasannya adalah karena kartel
mempunyai bentuk yang berbeda-beda dan pelaku kartel
Universitas Indonesia
153
mempunyai tingkat respons yang berbeda terhadap sanksi
tertentu. Jika KPPU diberikan kewenangan untuk
menentukan sanksi yang tepat dalam kasus tertentu (baik
sanksi pidana penjara, pidana denda, maupun ganti
rugi), maka KPPU bisa meningkatkan efek jera dari
sanksi yang dijatuhkan.
Terkait poin (v), terkait rumus kartel pF>Ep, maka
ketentuan UU No.5/1999 harus mampu meningkatkan
kemungkinan (a) mendeteksi adanya kartel dan
membuktikan kejahatan kartel (p atau probability) dan (b)
sanksi atas kartel (F atau Fines). Jika keuntungan yang
diharapkan dari kejahatan (Ep atau Estimated Profits) lebih
kecil daripada pF maka pelaku kartel akan lebih memilih
untuk mengaku bersalah daripada menjalankan kartel.
Keseluruhan poin (i) sampai dengan (v) dimaksudkan
untuk menciptakan kondisi prisoner’s dilemma dimana
terhadap setiap pelaku kartel diberikan penawaran
amnesti dan jika mereka tidak mengaku sementara pelaku
kartel lainnya mengaku maka kemungkinan tertangkapnya
pelaku kartel dan hukuman yang dijatuhkan terhadap
pelaku kartel tersebut akan lebih besar. Prinsip
fundamental prisoner’s dilemma yang harus diperhatikan
adalah bahwa dalam kondisi apapun (baik pelaku kartel
lain mengaku ataupun tidak), pelaku kartel tersebut
akan selalu berada dalam kondisi yang lebih baik
(hukumannya paling ringan) jika ia mengaku (Lihat bagan
Universitas Indonesia
154
I, bagan II dan bagan III dalam butir 4.1.2. Skripsi
ini).
Selanjutnya, strategi prisoner’s dilemma akan membantu
dalam menentukan ukuran sanksi atas kartel. Secara
konseptual, dalam kerangka prisoner’s dilemma, sanksi yang
dijatuhkan terhadap kartel harus memperhatikan
keterkaitan antara sanksi yang satu dengan yang lain.
Contohnya, asumsi bahwa pelaku usaha lebih takut
dipenjara daripada dikenakan denda merupakan asumsi
yang tidak sepenuhnya tepat. Pada umumnya, asumsi ini
yang digunakan dalam merumuskan sanksi pidana penjara.
Dengan kata lain, strategi prisoner’s dilemma memungkinkan
otoritas persaingan usaha untuk mengukur lamanya waktu
penjara, besaran sanksi pidana denda, dan besaran ganti
rugi perdata. Ukuran penentuan sanksi menjadi lebih
jelas ketika ada pembandingnya, yaitu sanksi lain.
Tarik-menarik ketiga sanksi di atas akan membantu KPPU
untuk menemukan titik keseimbangan (ekuilibrium) sanksi
dengan besaran sanksi yang proporsional untuk setiap
jenis sanksi.
4.4. Kerancuan dan/atau Absurditas Penentuan Sanksi
Terhadap Kartel Berdasarkan UU No. 5/1999
Berbeda dengan kajian mendalam dan pertimbangan
matang yang dilakukan oleh legislator di Amerika
Serikat, legislator di Indonesia terkesan tidak
melakukan kajian hukum dan ekonomi yang cukup dalam
Universitas Indonesia
155
menentukan sanksi pidana penjara maupun denda terhadap
kartel. Bahkan klasifikasi kartel sebagai kejahatan
atau pelanggaran saja tidak jelas. Hal ini menunjukkan
betapa semrawutnya penentuan suatu perbuatan sebagai
tindak pidana dalam UU. No.5/1999. Berikut akan
dijabarkan beberapa masalah terkait pasal 47 dan 48 UU
No. 5 tahun 1999.
Pasal 47 tentang Tindakan Administratif
(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa
tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang
melanggar ketentuan Undang-undang ini.
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat berupa:
a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13,
Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan
integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14; dan atau
c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan
kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek
monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha
tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan
atau
d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan
penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
Universitas Indonesia
156
e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau
peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua
puluh lima miliar
Pasal 48 tentang Pidana Pokok
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal
9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan
Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam
pidana denda serendah-rendahnya Rp
25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan
pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai
dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan
Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam
pidana denda serendah-rendahnya Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
setinggi-tingginyaRp 25.000.000.000,00 (dua puluh
lima miliar rupiah), atau pidana kurungan
pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
Universitas Indonesia
157
4.4.1 Pasal 47 dan 48 tidak merumuskan secara jelas
subyek sanksi.
Kata “pelaku usaha” dalam semua ketentuan UU No.
5/1999 merujuk pada orang-perseorangan atau
perusahaan.190 Permasalahan utama adalah apakah ketika
suatu perusahaan melakukan kartel maka yang menjadi
subyek sanksinya adalah perusahaan tersebut atau
individunya, misalnya direksi. Implikasinya dari tidak
jelasnya subyek tersebut sangat luas.
1. Apakah sanksi dijatuhkan kepada individu tersebut
atau perusahaannya? Jika dijatuhkan kepada
individu tersebut (dalam bentuk sanksi pidana
denda) maka termasuk semua harga pribadi individu
tersebut. Hal ini tidak masuk akal mengingat dalam
struktur perusahaan individu, misalnya direksi,
melakukan sesuatu berdasarkan anggaran dasar dan
demi kepentingan perusahaan.
2. Jika sanksi pidana tersebut dijatuhkan kepada
perusahaannya dan perusahaan tersebut gagal
membayar denda, apakah mungkin suatu perusahaan
bisa dikerangkeng (dikarenakan kurungan
pengganti)?
190 Pasal 1 butir 5 UU No. 5/1999 menyatakan:
Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha,baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangdidirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayahhukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-samamelalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalambidang ekonomi.
Universitas Indonesia
158
3. Jika ada dikhotomi sanksi terhadap orang-
perseorangan dan perusahaan, dimana batas tanggung
jawab masing-masing subyek? Pasal 47 dan 48 tidak
menjelaskan sama sekali tentang dikhotomi ini.
4. Apakah terdapat satu feit bisa dikenakan sanksi
(hukuman) terhadap 2 (dua) subyek sekaligus, yaitu
orang-perseorangan, misalnya direksi, dan
perusahaannya?
Poin mengenai subyek sanksi sangat penting untuk
diperhatikan karena sanksi tersebut harus dijatuhkan
kepada subyek yang tepat.
4.4.2 Sanksi pidana penjara untuk orang-
perseorangan dihilangkan
Pasal 48 merumuskan ketentuan sanksi dengan sanksi
pidana denda, bukan sanksi pidana penjara. Pasal 10
KUHP mengatur tentang pidana pokok dan pidana
tambahan.191 Dalam rumusan suatu ketentuan pidana,
terdapat perbedaan antara ancaman pidana penjara dengan
kurungan pengganti. Pidana penjara merupakan hukuman
pokok yang dijatuhkan ketika delik (unsur) pasal
tertentu terpenuhi dengan pidana penjara maksimum 15
(lima belas) tahun. Sementara itu, kurungan pengganti
adalah kurungan yang dijatuhkan ketika seseorang tidak191 Pidana pokok meliputi pidana mati, penjara, kurungan,
denda, dan tutupan. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak-haktertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumumanputusan hakim.
Universitas Indonesia
159
membayar pidana denda dengan kurungan maksimum 6 (enam)
bulan kecuali jika terdapat perbarengan atau berlakunya
pasal 52 KUHP.192 Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (2)
KUHP yang menentukan “Jika pidana denda tidak dibayar,
ia diganti dengan pidana kurungan.”
Contoh pasal yang hanya menentukan pidana penjara
adalah pasal 338 KUHP, yang menyatakan “Barang siapa
dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama
lima belas tahun.” Contoh pasal yang menentukan
alternatif antara pidana penjara dan pidana denda
adalah pasal 219 KUHP yang menyatakan “Barang siapa
secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dihaca
atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa
yang berwenang atau menurut, ketentuan undang-undang,
dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan orang
mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana
penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
Contoh pasal yang hanya menentukan pidana denda adalah
pasal 48 UU No. 5/1999.
Logika yang sama dengan poin pertama di atas
berlaku di sini. Apakah alasan pasal 48 tidak
menentukan pidana penjara karena subyek UU No. 5/1999
adalah perusahaan sehingga suatu perusahaan tidak
mungkin dikerangkeng (dikurung)? Jika ini adalah
192 Pasal 30 ayat (5) KUHP.
Universitas Indonesia
160
alasannya, alasan tersebut masih tidak masuk akal
karena hukuman pengganti atas pidana denda adalah
kurungan pengganti. Pertanyaan yang sama, jika
perusaahan tersebut tidak membayar pidana denda apakah
suatu perusahaan mungkin dikurung (dikerangkeng)?
4.4.3 Absurditas penentuan “denda” administrasi dan
“denda” pidana
Apa perbedaan istilah “denda” pada pasal 47 ayat
(2) butir g dengan istilah “pidana denda” pada pasal 48
ayat (1) dan (2)? Memang benar konsep sanksi
administrasi dengan pidana terkait dengan denda
mempunyai tujuan yang berbeda, namun perbedaan tersebut
tidak tercermin dalam perumusan pasal 47 dan 48. Nilai
denda administrasi adalah minimal Rp 1 (satu) milyar
dan maksimal Rp 25 (dua puluh lima) milyar. Nilai denda
pidana adalah (i) berdasarkan Pasal 48 ayat (1) minimal
Rp 25 (dua puluh lima) milyar dan maksimal Rp 100
(seratus) milyar, dan (ii) berdasarkan Pasal 48 ayat
(2) minimal Rp 5 (lima) milyar dan maksimal Rp 25 (dua
puluh lima) milyar. Apakah hukuman denda administrasi
dan pidana denda bisa dijatuhkan sekaligus yang
menyebabkan nilai maksimum denda (denda administrasi
dan pidana) menjadi Rp 50 (lima puluh) milyar atau Rp
125 (seratus dua puluh lima) milyar? Jika sanksi pidana
dikehendaki sebagai ultimum remedium, seharusnya
diantara pasal 47 dan 48 bisa diselipkan kalimat
Universitas Indonesia
161
“Sanksi pidana dijatuhkan jika dan hanya jika sanksi
administrasi telah dijatuhkan dan terbukti tidak
efektif dan/atau efisien mengoreksi sikap-tindak pelaku
usaha.”
Prinsip ultimum remedium memang menyatakan bahwa
pidana harus merupakan alternatif terakhir setelah
penyelesaian lainnya gagal atau tidak efektif. Namun,
prinsip ultimum remedium dalam konteks tersebut adalah
terkait dengan pengertian bahwa (i) sanksi administrasi
berbeda dengan sanksi pidana, dan (ii) sanksi pidana
lebih berat dibandingkan sanksi administratif. Sanksi
pidana dalam konteks ultimum remedium terkait erat
dengan sanksi pidana penjara yang dianggap sebagai
sanksi yang sangat berat karena merenggut hak asasi
manusia atas kebebasan dirinya. Selain itu, prosedur
pemeriksaan tindak pidana juga lebih merenggut lebih
banyak hak-hak asasi si tersangka maupun terdakwa,
yaitu dengan adanya prosedur penahanan,193
193 Berdasarkan Pasal 1 ayat (21) Kitab Undang-undang HukumAcara Pidana, “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwadi tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakimdengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diaturdalam undang-undang ini.”
Universitas Indonesia
162
penangkapan,194 penyitaan,195 penggeledahan badan,196
penggeledahan rumah,197 dan pada akhirnya penghukuman.
Pertanyaannya adalah apakah prinsip ultimum remedium
dalam arti dan konteks di atas berlaku terhadap
ketentuan pidana UU No. 5/1999 yang tidak merumuskan
pidana penjara? Sanksi pidana dalam Pasal 48 dan 49
hanya hampir sama sifat dan beratnya dengan sanksi
administrasi dalam Pasal 47,
4.4.4 Metode penghitungan lama kurungan akibat
tidak dibayarnya pidana denda dalam Pasal 48 UU
No. 5/1999 tidak sesuai dengan metode
194 Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-undang HukumAcara Pidana, “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupapengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwaapabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan ataupenuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yangdiatur dalam undang-undang ini.”
195 Berdasarkan Pasal 1 ayat (16) Kitab Undang-undang HukumAcara Pidana, “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidikuntuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannyabenda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujuduntuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan danperadilan.”
196 Berdasarkan Pasal 1 ayat (18) Kitab Undang-undang HukumAcara Pidana, “penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untukmengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untukmencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanyaserta, untuk disita.”
197 Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Kitab Undang-undang HukumAcara Pidana, “penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untukmemasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untukmelakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan ataupenangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”
Universitas Indonesia
163
penghitungan yang ditentukan pasal 30 ayat (4)
KUHP.
Penjelasan pada bagian ini akan dibagi ke dalam 2
(dua) bagian, yaitu (i) tentang absurditas metode
penghitungan yang ditetapkan legislator, dan (ii)
absurditas metode penghitungan yang diterapkan oleh
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”).
Terkait dengan poin (i), kekurangan lain UU
No.5/1999 adalah terkait dengan ketidaksesuaian metode
penghitungan lama kurungan akibat tidak dibayarnya
pidana denda dalam Pasal 48 UU No. 5/1999 dengan metode
penghitungan yang ditentukan pasal 30 ayat (4). Pasal
30 ayat (4) KUHP menyatakan:
“Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan
pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya
tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di
hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima
puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di
hitung paling banyak satu hari demikian pula
sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh
sen.”
Untuk mengatasi disparitas nilai nominal uang
antara waktu dibuatnya KUHP dengan masa sekarang bisa
digunakan metode penghitungan emas, yaitu dengan
menghitung berapa gram emas yang bisa didapatkan dengan
Universitas Indonesia
164
nilai nominal KUHP (misalnya Rp 7 dan 25 sen), dan
kuantitas gram emas tersebut dikalikan dengan harga
emas yang berlaku sekarang. Pertanyaannya adalah apakah
cara penghitungan ini diterapkan oleh legislator dalam
menghitung batas minimum dan maksimum pidana denda
berdasarkan Pasal 48 UU No. 5/1999?
Ironisnya adalah pidana denda Rp. 25 milyar itu
hanya sepadan dengan hukuman kurungan pengganti 6
(enam) bulan penjara, sementara dalam kasus Nenek Minah
yang mencuri kakao yang nilainya jauh di bawah Rp. 25
milyar, namun dihukum penjara 1 tahun 15 hari dengan
masa percobaan selama 3 bulan.198
Yang paling tidak masuk akal adalah, berdasarkan
Pasal 47 ayat (2) f , KPPU pernah memutuskan untuk
menghukum Para Terlapor membayar ganti rugi perdata
(damage) yang mirip dengan konsep ganti rugi pada Pasal
1365 KUHPerdata. Hukuman pembayaran ganti rugi tersebut
diputuskan KPPU dalam kasus kartel fuel surcharge Industri
Jasa Penerbangan Domestik.199
Dalam pembacaan putusan tersebut, KPPU menyatakan:
“...
198 Bisa dilihat dihttp://www.detiknews.com/read/2009/11/19/152435/1244955/10/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari. Kunjunganterakhir 7 Juni 2010.
199 Pembacaan Putusan Perkara Penetapan Harga Fuel Surchargedalam Industri Jasa Penerbangan Domestik. Bisa dilihat dihttp://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=1139&encodurl=06%2F07%2F10%2C12%3A06%3A32. Kunjunganterakhir tanggal 7 Juni 2010.
Universitas Indonesia
165
15. Menghukum Terlapor I, PT Garuda Indonesia
(Persero) membayar ganti rugi sebesar Rp.
162.000.000.000,- (seratus enam puluh dua milyar
rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai
setoran pendapatan ganti rugi pelanggaran di
bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah
dengan kode penerimaan 423755;
16. Menghukum Terlapor II, PT Sriwijaya Air
membayar ganti rugi sebesar Rp. 60.000.000.000,-
(enam puluh milyar rupiah) yang harus disetor ke
Kas Negara sebagai setoran pendapatan ganti rugi
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan
Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui
bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755;
17. Menghukum Terlapor III, PT Merpati Nusantara
Airlines (Persero) membayar ganti rugi sebesar Rp.
53.000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah)
yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran
pendapatan ganti rugi pelanggaran di bidang
persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas
Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan
kode penerimaan 423755
...”
Permasalahan utama adalah apakah ada dasar hukum
bagi KPPU untuk menentukan hukuman ganti rugi perdata?
Ganti rugi perdata merupakan hak orang-perseorangan
Universitas Indonesia
166
atau badan hukum dalam hubungan perdata yaitu antara
orang-perseorangan atau badan hukum dengan orang
perseorangan atau badan hukum. KPPU mewakili negara
Indonesia dalam mengawasi persaingan usaha di
Indonesia. Oleh karena itu, KPPU hanya berwenang
memutuskan sanksi denda administrasi, yaitu maksimal
Rp. 25 milyar, berdasarkan pasal 47 ayat (2) g UU
No.5/1999.
Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan:
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk
menggantikan kerugian tersebut.”
Unsur paling penting yang harus diperhatikan adalah
“membawa kerugian bagi orang tersebut” yang artinya
orang yang berhak atas ganti rugi adalah orang yang
dirugikan. Apakah KPPU dirugikan (dalam arti Pasal 1365
KUHPerdata) dalam kasus fuel surcharge maskapai
penerbangan? Jika argumen KPPU adalah bahwa KPPU
mewakili para konsumen melakukan class action untuk
menggugat industri jasa penerbangan atas sejumlah ganti
rugi, apa dasar hukumnya dan apakah ada prosedur dimana
uang ganti rugi tersebut akan didistribusikan kepada
para konsumen yang telah dirugikan menurut KPPU?
Bagaimana cara membagi uang tersebut kepada konsumen
dan cara menghitung porsi masing-masing individu?
Universitas Indonesia
167
4.5. Kaitan Antara Penentuan Sanksi Pidana Penjara,
Pidana Denda, dan/atau Ganti Rugi Perdata Dalam
Strategi Prisoner’s Dilemma Dengan Prinsip Ultimum
Remedium
Tarik-menarik sanksi pidana penjara, pidana denda,
dan/atau ganti rugi perdata dalam strategi prisoner’s
dilemma mempengaruhi cara kita memandang prinsip
ultimum remedium. Pada dasarnya, prinsip ultimum
remedium menyatakan bahwa jika suatu masalah (konflik)
bisa diselesaikan dengan penyelesaian di luar
penyelesaian pidana, maka cara itu harus ditempuh lebih
dahulu sebelum pendekatan sanksi pidana digunakan.
Dengan kata lain, jika penyelesaian lain (misalnya
perdata) lebih efektif dan/atau efisien daripada
penyelesaian/sanksi pidana, maka penyelesaian lain
(misalnya perdata) harus ditempuh dulu sebelum
penyelesaian/sanksi pidana diterapkan. Strategi
prisoner’s dilemma (seperti yang dijelaskan dalam butir
4.1 dan 4.2) digunakan untuk mengukur apakah
penyelesaian perdata, dalam konteks kartel, lebih
efektif dan/atau efisien daripada penyelesaian/sanksi
pidana penjara.
Nilai filsafat yang terkandung dalam prinsip
ultimum remedium adalah bahwa sanksi pidana
berorientasi pada filsafat utilitarianisme, yaitu
filsafat yang menekankan pada manfaat dari suatu
Universitas Indonesia
168
tindakan, sehingga suatu sanksi pidana harus membawa
manfaat yang lebih daripada sanksi lainnya jika sanksi
pidana tersebut diterapkan.
Alasan mengapa sanksi pidana dipandang efektif
dalam hal fungsi hukum pidana untuk menimbulkan efek
jera (deterrent) dan kelumpuhan (incapacitation) adalah
karena sanksi pidana merupakan sanksi yang paling berat
karena merenggut hak asasi manusia atas kemerdekaan
dirinya (tubuhnya). Oleh karena itu, sanksi pidana
dianggap lebih menakutkan daripada sanksi lain,
misalnya pidana denda, sanksi perdata atau
administrasi.
Asumsi di atas tidak lagi tepat (kontekstual) jika
dikaitkan dengan kartel. Pertama, penyelesaian di luar
pidana belum tentu merupakan bentuk sanksi yang paling
efektif karena bagi sebagian makhluk ekonomi dan
rationally self-interest, sanksi perdata atau denda lebih
memberatkan daripada sanksi pidana penjara. Dengan kata
lain, ada orang yang lebih memilih untuk dimasukkan ke
penjara daripada harus kehilangan sejumlah uang
tertentu. Raison d’être dari hukuman pidana denda atau
ganti rugi adalah karena korporasi merupakan makhluk
(spesies) ekonomi dengan tujuan utama dan satu-satunya:
keuntungan, maka yang mendera (menyakiti), melumpuhkan
(incapacitate), dan membuat jera korporasi adalah
kehilangan uang. Terkait alasan melumpuhkan, korporasi
beroperasi dengan menggunakan uang (atau modal atau
Universitas Indonesia
169
kapital) sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau
pelanggaran. (incapacitate), alasan kejahatan korporasi
seperti kartel disebut sebagai white collar crime adalah
karena kemampuan keuangannya yang besar sehingga
korporasi mampu menciptakan trik dan strategi yang
sangat kompleks untuk menghindari jeratan hukum
sehingga otoritas (pihak berwajib) sangat kewalahan
dalam mendeteksi maupun menginvestigasi kejahatan
korporasi tersebut. Oleh karena itu, kehilangan uang
akan melumpuhkan korporasi dalam melakukan kejahatan.
Kedua, prinsip utiliritanisme tidak tercermin dalam
sanksi penjara atau denda semata tanpa mempertimbangkan
fakta, situasi, dan kondisi yang ada dalam kasus
tertentu. Dikarenakan setiap orang mempunyai tingkat
ketakutan yang berbeda atas sanksi pidana penjara dan
perdata/denda, maka sanksi yang dikenakan atas
kejahatan kartel juga harus fleksibel mengikuti rasa
takut yang subyektif tersebut.
Kekeliruan hukum persaingan Indonesia adalah dengan
kaku menerapkan sanksi denda sebagai metode sanksi
paling efektif berdasarkan pasal 47 dan 48 UU No.5/1999
karena mengasumsikan bahwa pelaku usaha lebih takut
akan sanksi pidana denda daripada penjara (dijelaskan
dengan lebih rinci di poin 4.4).
Universitas Indonesia
170
BAB VPENUTUP
5.1 Simpulan
Beberapa simpulan dari penjelasan Skripsi ini
adalah sebagai berikut.
1. Dasar kriminalisasi/pemidanaan kartel yang diatur
oleh Pasal 11 juncto Pasal 48 UU No. 5/1999 masih
tidak jelas, tidak konsisten dengan asas-asas hukum
pidana yang diatur dalam KUHP, serta tidak pernah
dikaji dengan baik sehingga baik secara normatif
maupun praktik terjadi kesemrawutan.
2. Suatu perbuatan dikriminalisasi karena dampak buruk
(harm dan damage) yang ditimbulkan. Harm meliputi
nilai moral dan/atau sosial yang tidak bisa diukur
dengan kerugian finansial semata. Sementara damage
meliputi kerugian yang bersifat finansial (monetary
compensation). Selain itu, suatu perbuatan
dikriminalisasi karena menyebabkan rasa tidak
tenteram dan tidak aman dalam masyarakat. Secara
umum, kartel merupakan kegiatan anti persaingan
usaha yang dilarang paling keras oleh OECD. RIA
Selandia Baru 2010 tentang kartel menjelaskan bahwa
kartel dikrimnalisasi karena (i) harm dan damage
besar yang ditimbulkannya terutama terhadap ekonomi
dan konsumen, hilangnya efisiensi ekonomi akibat
kartel, dan kemiripan analogis dan asosiatif dengan
Universitas Indonesia
171
pencurian yang merupakan hard-core of criminality. Lebih
buruk lagi, kartel merupakan white collar-crime yang
sangat sulit dideteksi apalagi ditangkap serta
menimbulkan kerugian uang yang besar bukan hanya
terhadap konsumen sebagai orang-perseorangan, namun
juga merenggut kebebasan ekonomi konsumen, hak
penghidupan yang layak dari pelaku usaha lain,
serta kesejahteraan umum. Anne K. Bingman (otoritas
persaingan usaha Amerika Serikat) menyatakan bahwa
“pelaku yang melakukan tender kolusif (salah satu
bentuk kartel), membagi pasar atau menetapkan harga
mengambil uang dari kantong konsumen Amerika
Serikat dan mencuri uang dari ‘mesin kasir’ bisnis
Amerika, dan ini sama saja dengan merampok sebuah
rumah di malam hari dengan masuk secara diam-diam
dalam kegelapan.”
3. Strategi prisoner’s dilemma menggambarkan tarik-menarik
antara penentuan sanksi pidana penjara, denda, dan
ganti rugi perdata atas kartel. Strategi ini sangat
berguna dalam menerapkan asas ultimum remedium
karena mampu mengukur tingkat efektifitas dan
efisiensi sanksi sehingga otoritas persaingan usaha
maupun legislator mampu menentukan dengan timbangan
yang lebih akurat sanksi mana yang dipakai untuk
menangani kartel. Otoritas Amerika Serikat mengukur
tingkat efektifitas dan efisiensi sanksi dengan
menerapkan strategi prisoner’s dilemma. Strategi ini
Universitas Indonesia
172
mampu mengukur rasa takut dan insentif pelaku
kartel sehingga bisa ditentukan secara lebih akurat
sanksi mana yang lebih efektik dan efisien untuk
menangani kartel.
5.2 Saran
1. Hendaknya legislator melakukan kajian yang mendalam
dan ekstensif tentang dampak buruk (harm dan
damage) kartel sebelum mengkriminalisasikan
perbuatan tersebut. Kajian tentang dasar normatif
dan positivistik (aktual dan diukur berdasarkan
reaksi sosial) menciptakan hukum yang berwibawa dan
dipatuhi masyarakat. Selain itu, perbedaan denda
pidana (pasal 48) dan denda administrasi (pasal 47)
harus dinyatakan dengan tegas dalam UU No.5/1999.
Dalam menjatuhkan hukuman, KPPU harus menjelaskan
secara rinci dan tegas apakah denda pidana atau
administrasi yang dijatuhkan dalam perkara
persaingan usaha. Sebagai otoritas persaingan
usaha, KPPU mempunyai peran yang penting dalam
menegakkan hukum persaingan usaha. Oleh karena itu,
KPPU harus memberikan pertimbangan hukum yang jelas
tentang perhitungan jumlah sanksi denda.
2. Strategi prisoner’s dilemma bisa diterapkan KPPU untuk
menangani perkara kartel secara lebih efektif dan
efisien. Selain itu, strategi tersebut juga bisa
membantu KPPU dalam mengukur efektifitas dan
Universitas Indonesia
173
efisiensi sanksi pidana penjara, pidana, dan ganti
rugi perdata sehingga KPPU mampu menentukan kapan
sanksi pidana penjara harus diterapkan dan berapa
lama durasi hukuman penjaranya.
3. Legislator harus memasukkan ketentuan sebagai
berikut dalam UU No.5/1999 untuk menerapkan
strategi prisoner’s dilemma. Pertama, ketentuan tentang
amnesti bagi pelaku usaha pertama yang mengaku
terlibat dalam kartel dan membantu KPPU dalam
proses investigasi kartel yaitu dengan tidak
dituntutnya pelaku kartel atas pertanggungjawaban
pidana. Kedua, ketentuan yang menyatakan bahwa
pengakuan keterlibatan kartel secara otomatis
membuktikan kesalahan pelaku kartel sehingga pihak
yang merasa dirugikan secara perdata (misalnya
konsumen) tidak perlu unsur kesalahan/melawan hukum
di pengadilan perdata. Ketiga, ketentuan tentang
fleksibilitas penjatuhan hukuman oleh KPPU baik
sanksi denda pidana, ganti rugi perdata, maupun
sanksi pidana penjara. Keempat, ketentuan tentang
besaran denda administrasi, ganti rugi perdata,
sanksi pidana denda maupun sanksi pidana penjara
dengan mempertimbangkan faktor tingkat efek jera
dari masing-masing sanksi.
4.
Universitas Indonesia
174
DAFTAR PUSTAKA
I. Buku dan Jurnal
Allen, Michael J. Textbook on Criminal Law. Edisi ke-9. (Newyork: Oxford University Press,2007).
Ancel, Marc. Social Defence. 1965 dalam Arief, BardaNawawi. Bunga Rampai Kebijakan HukumPidana.Cetakan ke-II. (Jakarta: Citra AdityaBakti, 2002).
Andersen, William R. and C. Paul Rogers III.Antitrust Law: Policy and Practice. Edisi ke-3.(1999).
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan HukumPidana.Cetakan ke-II. (Jakarta: Citra AdityaBakti, 2002).
Ashworth, A. Principles of Criminal Law. Edisi ke-2.(Oxford: Clarendon, 1995).
Baker, Donald I. The Use of Criminal Law Remedies to Deterand Punish Cartels and Bid-Rigging. 69 GeorgetownWashington Law Review. 693, 701 (2001).seperti dikutip Christopher R. Leslie.Symposium The Antitrust Enterprise:Principle and Execution. Antitrust Amnesty,Game Theory, and Cartel Stability, Journal of CorporationLaw. 31 J. Corp. L. 453. 2006.
Bemmelen, J M. Van. Criminoligie, leerboek dermisdaadkunde. Cetakan ke-4. (Zwolle, 1958)
Universitas Indonesia
175
dalam Roeslan Saleh Dari Lembaran KepustakaanHukum Pidana. (Sinar Grafika: 1988).
Bianchi, H. Stigmatisering. Deventer. 1971 dalamRoeslan Saleh Dari Lembaran Kepustakaan HukumPidana. (Sinar Grafika: 1988).
Brodeur, Jean-Paul dan Geneviève Ouellet. What Isa Crime? A Secular Answer. (Canada: UBC Press,2004).
Cross, H. A Theory of Criminal Justice. (1979).
Devlin, P. The Enforcement of Morals. (Oxford: OUP,1965).
Durkheim, Émile. Deux lois de l’évolution pénale L’annéesociologique. (1899-1900). Dalam Jean-PaulBrodeur dan Geneviève Ouellet. What Is aCrime? A Secular Answer. (Canada: UBC Press,2004).
Fletcher, Daniel J. The Lure of Leniency: MaximizingCartel Deterrence in Light of La Roche V. Empagran andthe Antitrust Criminal Penalty Enhancement and ReformAct of 2004. Transnational Law andContemporary Problems, University of IowaCollege of Law. 2005. 15 Transnat'l L. &Contemp. Probs. 341.
Garofalo, Barone Raffaele. Criminology (1885).Disadurkan Montclair (New Jersey: PattersonSmith Reprints, 1968).
Ginsburg, Tom & Richard H. McAdams. Adjudicating inAnarchy: An Expressive Theory of International DisputeResolution. 45 Wm. & Mary Law Review. 1229,1245-49 (2004) seperti dikutip dalamChristopher R. Leslie. Symposium TheAntitrust Enterprise: Principle andExecution. Antitrust Amnesty, Game Theory, and
Universitas Indonesia
176
Cartel Stability, Journal of Corporation Law. 31 J.Corp. L. 453. 2006.
Hafild, Emmy, Daris Furqon, et.al. Addicted to Loan:The World Bank Foot Prints in Indonesia. WALHI(Indonesian Forum for Environment). Lihathttp://www.asienhaus.de/public/archiv/WB-and_Indonesia_Walhi_paper.pdf. Kunjunganterakhir 22 Juni 2010.
Hamzah, A. Hukum Pidana Ekonomi. Edisi Revisi.(Jakarta: Erlangga,1996).
Hansen, Knud, Peter W. Heermann, et.al. KomentarHukum Undang-Undang tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Edisikedua (Jakarta: Deutsche Gesellschaft fürTechnische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH danPenerbit Katalis, 2002)
Harrision, Glenn dan Matthew Bell. RecentEnchancements in Antitrust Criminal Enforcement: BiggerSticks and Sweeter Carrots. Houston Business andTax Law Journal. 2006. 6 Hous. Bus. & Tax.L.J. 207.
Hart HLA. Law, Liberty and Morality. (Oxford: OUP,1963).
Hoefnagels, G. Peter. The Other Side of Criminology.1969 Arief, Barda Nawawi. Bunga RampaiKebijakan Hukum Pidana.Cetakan ke-II. (Jakarta:Citra Aditya Bakti, 2002).
Kobayashi, Bruce H. Antitrust, Agency, and Amnesty: AnEconomic Analysis of the Criminal Enforcement of theAntirust Laws Against Corporations. 69 GeorgeWashington Law Review. 715 (2001) sepertiyang dikutip dalam Daniel J. Fletcher. TheLure of Leniency: Maximizing Cartel Deterrence in Light ofLa Roche V. Empagran and the Antitrust Criminal Penalty
Universitas Indonesia
177
Enhancement and Reform Act of 2004. TransnationalLaw and Contemporary Problems, Universityof Iowa College of Law. 2005. 15 Transnat'lL. & Contemp. Probs. 341.
Lande, Robert H. Why Antitrust Damage Levels Should BeRaised. 16 Loy. Consumer Law Review. 329(2004) seperti dikutip dalam Christopher R.Leslie. Symposium The Antitrust Enterprise:Principle and Execution. Antitrust Amnesty,Game Theory, and Cartel Stability, Journal of CorporationLaw. 31 J. Corp. L. 453. 2006.
Langmeyer. Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte desrechts. 2 edruk dalam Roeslan Saleh DariLembaran Kepustakaan Hukum Pidana. SinarGrafika (1988).
Leslie, Christopher R. Symposium The AntitrustEnterprise: Principle and Execution.Antitrust Amnesty, Game Theory, and Cartel Stability,Journal of Corporation Law. 31 J. Corp. L. 453.2006.
Leslie, Christopher R. Trust, Distrust, and Antitrust. 82Texas Law Review. 643-45 (2004).
Lubis, Andi Fahmi, Anna Maria Tri Anggraini,et.al. Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks danKonteks. (Indonesia: Deutsche Gesellschaftfür Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH,2009).
Mamudji, Sri et al. Metode Penelitian dan PenulisanHukum. (Jakarta: Badan Penerbit FakultasHukum Universitas Indonesia, 2005).
Mason, Christopher. The Art of the Steal. 199 (2004)seperti dikutip dalam, Christopher R.Leslie. Symposium The Antitrust Enterprise:Principle and Execution. Antitrust Amnesty,
Universitas Indonesia
178
Game Theory, and Cartel Stability, Journal of CorporationLaw. 31 J. Corp. L. 453. 2006.
Molan, Mike, Denis Lanser, dan Duncan Bloy.Principles of Criminal Law. Edisi ke-4. (BritaniaRaya: Cavendish Publishing, 2000).
Nusantara, Abdul Hakim Garuda. Mengkritisi RUUKUHPidana dalam perspektif HAM, Konsultasi Publik “.Perlindungan HAM Melalui Reformasi KUHP. ”Hotel Santika Slipi Jakarta, 3 - 4 Juli2007. Kerjasama KOMNAS HAM dan AliansiNasional Reformasi Indonesia.
Ohanga, Manatu. Cartel Criminalisation. Ministry of EconomicDevelopment, Discussion Document for Regulatory ImpactAssessment. (Ministry of EconomicDevelopment: New Zealand, January 2010).
Packer, Herbert. The Limits of the Criminal Sanction. (CA:Stanford UP, 1968).
Saleh, Roeslan. Dari Lembaran Kepustakaan HukumPidana. Sinar Grafika (1988).
Rizer, George. Sosiologi: Ilmu PengetahuanBerparadigma Ganda. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) seperti dikutipdalam Eva Achjani Zulfa Keadilan Restoratif diIndonesia (Studi tentang Kemungkinan PenerapanPendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek PenegakanHukum Pidana). Ringkasan Disertasi.(Jakarta: Universitas Indonesia, 2009).
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum.(Jakarta: UI Press, 2005).
Stephen. A History of Criminal Law of England. (1883).
Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat(Bandung: Sinar Baru, 1983) dalam Arief,
Universitas Indonesia
179
Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan HukumPidana.Cetakan ke-II. (Jakarta: Citra AdityaBakti, 2002).
Tappan, Paul W. Crime, Justice and Correction. (NewYork: McGraw-Hill Series in Sociology,1960).
Williams ,Glanville. The Definition of Crime. DalamCurrent Legal Problems oleh George W. Keeton danGeorge Schwarzenberger. University College.vol. 8, (London: Stevens and Sons, 1955).
Zulfa, Eva Achjani. Keadilan Restoratif di Indonesia (Studitentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan KeadilanRestoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana).Ringkasan Disertasi. (Jakarta: UniversitasIndonesia, 2009).
II. Hasil Kajian atau Laporan
OECD 2006. Hard Core Cartels – Third Report on theImplementation of the 1998 OECD Recommendationdalam OECD Journal of Competition Law and Policy.Vol 8.
OECD Recommendation of the Council Concerning Effective ActionAgainst Hard Core Cartels (diadopsi oleh Dewanpada rapat sesi 921 pada tanggal 25 Maret1998 [C/M (98) 7/PROV]).
Summart Report. Resource Material Series No. 7.UNAGERI. 1974
The Wolfenden Committee. Report of the Committee ofHomosexual Offences and Prostitution (1957).
III. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Universitas Indonesia
180
KPPU, Keputusan KPPU No. 3 tahun 2009 tentangPedoman Pelaksana Pasal 1 ayat 10 UU No. 5Tahun 1999 tentang Pasar Bersangkutan.
IV. Kamus
Garner, Bryan A. Blacks Law Dictionary. Edisi ke-8.(Thompson: United States, 1999).
V. Seminar atau Workshop
Bingman, Anne K. dan Gary R. Spratling. CriminalAntitrust Enforcement dalam Criminal Antitrust Law andProcedure WorkshopABA Section of Antitrust. HyattRegency Hotel Dallas. Texas. February 23,1995. Lihat dihttp://www.justice.gov/atr/public/speeches/0103.pdf (kunjungan terakhir 25 Mei 2010).
Blochm Robert E., Program Amnesti The Antitrust Division.Dipresentasikan pada the American BarAssociation's Section of Antitrust Law's Criminal AntitrustLaw and Procedure Workshop (Feb. 23-24, 1995).Lihat di http://www.mayerbrownrowe.com/publications/article.asp?id=841&nid=6 (kunjungan terakhir 29Mei 2010).
Hammond, Scott D. Direktur Criminal EnforcementAntitrust Division, Department of JusticeAmerika Serikat, A Summary Overview of theAntitrust Division's Criminal Enforcement Program.Dipresentasikan pada the New York State BarAssociation 1 (Jan. 23, 2003). Lihat dihttp://www.justice.gov/atr/public/speeches/200686.htm (kunjungan terakhir 30 Mei2010).
Universitas Indonesia
181
Hammond, Scott D. Direktur Criminal EnforcementAntitrust Division, Department of JusticeAmerika Serikat. Detecting and Deterring CartelActivity Through An Effective Leniency Program.Dipresentasikan pada the International Workshopon Cartels 10 (Nov. 21-22, 2000). Lihat dihttp://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/9928.pdf (kunjungan terakhir 30 Mei 2010).
Pate, R. Hewitt. Anti-cartel Enforcement: The Core AntitrustMission. Disampaikan kepada the British Institute ofInternational and Comparative Law pada Third AnnualConference on International and ComparativeCompetition Law (May 16, 2003). Lihat:http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/201199.htm (kunjungan terakhir tanggal 20 Mei2010).
Spratling, Gary R, Asisten Deputi AttorneyGeneral, U.S. Department of Justice, Are theRecent Titanic Fines in Antitrust Cases Just the Tip of theIceberg? Dipresentasikan pada the American BarAssociation's Criminal Justice Section's Twelfth AnnualNational Institute tentang White Collar Crime (Mar.6, 1998). Lihat dihttp://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/212581.pdf (kunjungan terakhir 29 Mei 2010).
Spratling, Gary R. Asisten Deputi AttorneyGeneral Antitrust Division, Deparment ofJustice Amerika Serikat. Making Companies AnOffer They Shouldn't Refuse: The Antitrust Division'sCorporate Leniency Policy-An Update.Dipresentasikan pada the Bar Association of theDistrict of Columbia's 35th Annual Symposium onAssociations and Antitrust 3. (Feb. 16, 1999).Lihat di http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/2247.pdf.(kunjungan terakhir 30 Mei 2010).
Universitas Indonesia
182
Spratling, Gary R. Asisten Deputi AttorneyGeneral, U.S. Department of Justice. TheTrend Towards Higher Corporate Fines: It's a Whole NewBall Game. Ddipresentasikan pada the AmericanBar Association's Criminal Justice Section's EleventhAnnual National Institute tentang White Collar Crime(Mar. 7, 1997). Lihat dihttp://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/4011.pdf (kunjungan terakhir 29 Mei 2010).
VI. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan
Brief for Economists Joseph E. Stiglitz dan Peter R. Orszag sebagaiAmicus Curiae Supporting Respondents dalam kasusF. Hoffman-Laroche, Ltd. v. Empagran, 124S.Ct. 2349 (2004) (No. 03-724) seperti yangdikutip Daniel J. Fletcher. The Lure ofLeniency: Maximizing Cartel Deterrence in Light of LaRoche V. Empagran and the Antitrust Criminal PenaltyEnhancement and Reform Act of 2004. TransnationalLaw and Contemporary Problems, Universityof Iowa College of Law. 2005. 15 Transnat'lL. & Contemp. Probs. 341.
Corporate Leniency Policy (1993). Lihat di http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0091.htm (kunjungan terakhir 30 Mei 2010).
Director of Public Prosecutions v. Nock and Another. House ofLords AC 979 (1978).
Hoffman-Laroche, Ltd. v. Empagran. 124 Supreme Court2359, 2363 (2004).
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Universitas Indonesia
183
Indonesia. Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha TidakSehat.
Pfizer, Inc. v. Gov't of India, 434 U.S. 308 (1978).
Title 15 United States Code § 1 (2000).
Trade Practices Amendment (Cartel Conduct and other Measures)Bill 2008.
U.S. Sentencing Guidelines Manual § 2B (2004).
VII. Berita online
http://www.detiknews.com/read/2009/11/19/152435/1244955/10/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari. Kunjungan terakhir 7 Juni 2010.
Pembacaan Putusan Perkara Industri Minyak GorengSawit di Indonesia. Bisa dilihat dihttp://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=1140&encodurl=06%2F07%2F10%2C12%3A06%3A32. Kunjungan terakhir tanggal 7Juni 2010.
Pembacaan Putusan Perkara Penetapan Harga FuelSurcharge dalam Industri Jasa PenerbanganDomestik. Bisa dilihat dihttp://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=1139&encodurl=06%2F07%2F10%2C12%3A06%3A32. Kunjungan terakhir tanggal 7Juni 2010.
Universitas Indonesia