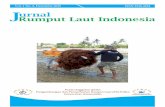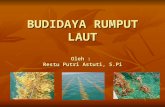Daftar Penyakit Pada Budidaya Ikan Laut di Indonesia
Transcript of Daftar Penyakit Pada Budidaya Ikan Laut di Indonesia
PENYAKIT IKAN AIR LAUT DI
INDONESIA
ROMI NOVRIADI RINI PURNOMOWATI
DODI YUNIANTO JOKO SANTOSA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA DIREKTORAT KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN 2014
I. Pendahuluan
a. Latar Belakang Pelaksanaan pembangunan sektor budidaya ikan laut pada dasarnya dapat dilakukan
dengan cepat, efektif dan menguntungkan karena memiliki berbagai kekuatan, peluang dan akses pasar yang cukup luas. Secara fisik, Kusumastanto (2003), menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang melimpah untuk pembangunan industri perikanan budidaya. Potensi tersebut meliputi wilayah perairan nasional seluas 3,1 juta km2, luas Zona Ekonomi Eksklusif sekitar 2.8 juta km2, panjang garis pantai mencapai 81.000 km dan memiliki jumlah pulau sebanyak 17.499 buah yang dapat digunakan untuk penguatan kapasitas produksi budidaya ikan laut. Berdasarkan data statistik KKP (2009), pemanfaatan potensi budidaya laut masih berkisar 0,3% dengan 12,502,396 Ha lahan potensi yang masih dapat dikembangkan. Kenaikan rata-rata produksi budidaya ikan laut dalam kurun waktu 2009-2010 juga meningkat sekitar 20% dengan nilai produksi mencapai 10,3 Triliun (KKP, 2009). Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang investasi dan pengembangan industri budidaya ikan laut di Indonesia cukup menjanjikan.
Pembangunan budidaya ikan laut menjadi sangat penting karena selain didukung oleh data potensi juga didasari oleh fakta bahwa kondisi sumberdaya perikanan Indonesia khususnya perikanan tangkap, telah mengalami over fishing pada beberapa daerah yang berakibat kepada adanya tren penurunan jumlah produksi. Untuk memperkuat kapasitas dan mempercepat proses peningkatan produksi, telah dilakukan program revitalisasi perikanan budidaya melalui kegiatan pengembangan kawasan minapolitan, komoditas unggulan dan penguatan modal yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing melalui pemberdayaan usaha budidaya kepada masyarakat dan perbaikan mutu hasil perikanan budidaya. Seluruh program ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan sinergi terhadap produktivitas sektor perikanan budidaya sehingga kebutuhan pangan (food security) khususnya bagi masyarakat Indonesia dapat terpenuhi.
Salah satu hambatan utama dalam keberlanjutan produksi budidaya adalah kematian yang diakibatkan oleh infeksi mikroorganisme patogen dan degradasi kualitas lingkungan. Kondisi ini berkorelasi positif dengan semakin intensifnya sistem budidaya yang dikembangkan (Cao et al., 2007). Secara global, potensi kerugian ekonomi akibat wabah penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi mikroorganisme patogen cukup signifikan dan berdampak kepada jumlah produksi, keuntungan dan keberlanjutan sistem budidaya. Kerugian ekonomi pada industri budidaya akibat wabah penyakit diperkirakan mencapai US$ 9 miliar per tahun (Subasinghe et al., 2001) dan berdampak kepada penurunan jumlah produksi ikan budidaya di seluruh dunia (Hill, 2005). Di Indonesia, Zafran et al., (1997) menyatakan bahwa infeksi oleh parasit Benedenia, Neobedenia, Diplectanum, Pseudorhabdosynochus, Haliotrema, Trichodina, Lepeophtheirus, dan Cryptocaryon irritans telah menjadi wabah umum pada ikan Kerapu. Sementara, infeksi yang disebabkan oleh iridovirus (Fris Johnny dan Des Roza, 2009) dan Nervous Necrosis Virus (NNV) (Sukadi, 2004) telah menjadi hambatan tersendiri bagi peningkatan jumlah produksi. Kondisi ini membuktikan bahwa masalah penyakit dalam perkembangan budidaya ikan laut memerlukan perhatian yang sangat serius.
Secara umum, jenis penyakit pada budidaya ikan laut dapat dibedakan menjadi 2
kelompok, yakni penyakit infeksius dan non-infeksius (Subasinghe, 2009). Penyakit infeksius disebabkan oleh organisme patogen dan mampu menyebar melalui pergerakan inang yang telah terinfeksi. Secara rinci, kelompok penyakit ini dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu penyakit parasitik, bacterial, viral dan mikotik. Sementara penyakit non-infeksius umumnya disebabkan oleh kondisi lingkungan, defisiensi nutrient, genetik, pengelolaan aktivitas budidaya yang buruk dan kontaminasi dari senyawa yang bersifat toksik. Disamping hal tersebut, organisme yang ada di lingkungan budidaya dan digolongkan sebagai “hama” pada kegiatan budidaya ikan laut juga dapat digolongkan sebagai penyebab penyakit non-infeksius.
Perhatian terhadap masalah penyakit ikan semakin meningkat sejalan dengan perubahan pola sistem budidaya yang menuju kearah intensifikasi. Informasi mengenai jenis, sumber dan siklus hidup penyakit yang sering menyerang ikan laut selain sangat membantu dalam upaya pengobatan juga bermanfaat dalam menentukan tindakan pencegahan yang harus dilakukan oleh para pembudidaya ikan untuk mencegah timbulnya wabah penyakit (Afrianto dan Liviawaty, 1992). Namun, informasi mengenai penyakit ikan laut secara ilmiah di Indonesia masih sangat terbatas dan hanya terdokumentasi secara parsial dalam laporan penelitian, jurnal, maupun buku-buku hasil kegiatan pemantauan penyakit ikan dan lingkungan. Menurut Mangunsuwiryo (1990), kurangnya informasi ini utamanya disebabkan oleh berbagai keterbatasan seperti kekurangan pakar mengenai penyakit ikan, fasilitas laboratorium, dan penyebaran informasi penyakit ke tingkat petambak/petani ikan. Hal ini menyebabkan informasi mengenai permasalahan penyakit secara lengkap dan terkini sulit diperoleh baik oleh masyarakat petani ikan, praktisi perikanan, dinas/lembaga terkait maupun para peneliti. Terbatasnya penyebaran informasi mengenai penyakit ikan ke tingkat petambak/petani ikan atau bahkan ke para pelaku bisnis ataupun praktisi bidang perikanan menyebabkan kesulitan dalam melakukan tindakan penanggulangan maupun cara pengobatan atau terapinya.
Adanya informasi yang cepat dan lengkap mengenai cara mengendalikan penyakit ikan sangat bermanfaat dalam upaya pengembangan penanggulangan penyakit ikan di Indonesia. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan menyusun tinjauan Penyakit Ikan Air Laut di Indonesia yang diharapkan dapat mendukung upaya pengendalian penyakit agar lebih terarah, sistimatis dan efektif sehingga mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat pembudidaya terhadap timbulnya wabah penyakit di dalam lingkungan media pemeliharaan. Tinjauan ini juga ingin memberikan pengertian bahwa penggunaan antibiotika untuk tindakan pengobatan sebaiknya mulai ditinggalkan. Karena selain dapat menyebabkan bakteri menjadi resisten terhadap beberapa antibiotik tertentu, penggunaan antibiotik juga menimbulkan ancaman terhadap kesehatan manusia berupa alergi dan keracunan melalui akumulasi antibiotik pada produk olahan ikan (Alderman dan Hastings, 1998). Akhirnya, penyusunan tinjauan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pelaksanaan prinsip pencegahan sebagai komponen utama dalam kegiatan industri budidaya ikan laut dan menggantikan prinsip pengobatan yang terbukti tidak terlalu efektif dalam mengendalikan penyakit ikan budidaya.
b. Maksud dan Tujuan Tujuan dari disusunnya tinjauan tentang penyakit ikan air laut di Indonesia ini adalah:
Sebagai acuan bagi masyarakat pembudidaya dan pengambil kebijakan untuk mengembangkan teknik diagnosa dan pengendalian penyakit yang tepat, efektif dan sistimatis
Sebagai acuan bagi petugas perikanan baik daerah maupun pusat untuk menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap timbulnya penyakit pada budidaya ikan laut di Indonesia.
II. Jenis-Jenis Penyakit Ikan Air Laut di Indonesia
Sakit pada ikan yaitu suatu keadaan abnormal yang ditandai dengan penurunan kemampuan ikan secara gradual dalam mempertahankan fungsi-fungsi fisiologik normal. Pada keadaan tersebut ikan dalam keadaan tidak seimbang dari sisi fisiologis dan tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan (Irianto, 2005). Sakit pada ikan umumnya timbul akibat interaksi dari 3 faktor, yakni inang, patogen dan lingkungan. Untuk itu pada bab ini akan secara khusus dibahas tentang jenis-jenis penyakit pada ikan air laut di Indonesia.
II.1 Penyakit Viral Virus merupakan agensia infeksi non seluler dan hanya dapat melakukan multiplikasi
dalam sel inang. Virus berukuran sangat kecil yaitu bervariasi dari 18-200 nm (Smail dan Munro, 1989), sehingga hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop electron. Untuk dapat bertahan hidup dilingkungan, virus harus mampu berpindah dari inang satu ke inang lainnya, menginfeksi dan replikasi pada inang yang sesuai. Sejumlah virus dapat berada dalam tubuh inang dalam waktu lama tanpa melakukan replikasi. Pada keadaan tersebut, genom virus dapat terintegrasi dalam kromosom inang. Dengan kondisi yang demikian, maka kehadiran virus dapat bersifat laten dan akan meledak sebagai wabah manakala ikan dalam kondisi lemah (Irianto, 2005). Beragam virus diketahui telah menginfeksi ikan air laut di Indonesia diantaranya: II.1.1 Nervous Necrosis Virus (NNV) Penyakit ini dikenal juga sebagai Viral encephalopathy and retinopathy (VER), Spinning
grouper diseases, Fish encephalitis atau Whirling disease (Lio-Po dan de la Pena, 2004). Penyebab penyakit ini adalah piscine nodavirus dari genus Betanodavirus dengan ukuran 25-30 nm. Piscine nodavirus terdiri atas 4 genotip: red-spotted grouper nervous necrosis virus (RGNNV), striped jack nervous necrosis virus (SJNNV), barfin flounder nervous necrosis virus (BFNNV) dan tiger puffer nervous necrosis virus (TPNNV). Penyakit ini menginfeksi seluruh tahapan perkembangan ikan, namun kematian tinggi dilaporkan terjadi pada larva dengan umur kurang dari 20 hari. Gejala klinis umum pada beberapa jenis ikan yang terinfeksi NNV menunjukkan perilaku
berenang ikan yang tidak beraturan, beberapa ikan tenggelam ke dasar bak dan kemudian mengapung lagi di permukaan. Induk dan benih ikan yang terinfeksi menunjukkan adanya pembengkakan gelembung renang (Gambar 1), letargik (sekarat, dengan gerakan lemah), warna tubuh terlihat lebih gelap dan hilang nafsu makan. Ikan yang terinfeksi NNV umumnya memperlihatkan keadaan gangguan saraf yang berhubungan dengan vakuolisasi (kerusakan) kuat sistem saraf pusat dan retina (Thierry et al., 2006).
Gambar 1. Induk ikan kerapu Epinephelus coioides dengan perut bengkak yang dikaitkan dengan infeksi VNN (Sumber: Lio-Po dan de la Pena, 2004)
Virus ini dapat ditularkan dari ikan yang terinfeksi ke ikan yang sehat dalam waktu 4 hari
kontak di media pemeliharaan. Nodavirus sebagai agen penyebab NNV dapat dideteksi pada ikan tanpa gejala klinis. Ikan tersebut dapat menjadi wadah virus dan dapat berperan menjadi sumber virus bagi larva mereka.
Tindakan pengendalian yang dapat dilakukan untuk menghindari ikan budidaya dari
infeksi NNV diantaranya adalah dengan: (1) menerapkan pengelolaan pemeliharaan dipanti benih secara ketat, (2) penggunaan benih dan induk yang memiliki sertifikat kesehatan ikan dan berasal dari panti benih yang memiliki sertifikasi CPIB, (3) menerapkan vaksinasi untuk memperkuat antibodi dan (4) mengurangi stress selama masa pemeliharaan.
II.1.2 Iridovirus
Iridovirus merupakan famili virus yang memiliki ukuran 130-300 nm, materi genetiknya berupa DNA dan dengan kapsid berbentuk ikosahedral (berisi 20). Iridovirus dijumpai pada beragam spesies ikan laut dan dapat ditemukan di limpa dan jaringan intestinal ikan yang sakit atau sekarat dengan tanda-tanda penyakit sistemik. Tingkat mortalitas ikan yang terinfeksi mulai dari rendah (0,5 – 10%) hingga sedang (50%) dan umumnya dapat menyebabkan kematian dalam kurun waktu 24-48 jam setelah munculnya gejala-gejala infeksi. Tanda-tanda klinis ditunjukkan oleh melanosis (warna tubuh gelap) dan letargik (sekarat, dengan gerakan lemah). Seringkali ikan kehilangan nafsu makan, pembengkakan abdomen, limpa membesar, saluran pencernaan memerah karena pendarahan (hemoragik) dan terdapat cairan keruh dalam rongga tubuh.
Infeksi iridovirus pada budidaya ikan laut telah diidentifikasi memiliki variasi yang dapat digolongkan menjadi: Red Seabream Iridovirus Disease (RSIVD), Sleepy Grouper Disease (SGD) dan Grouper Iridovirus Disease (GIVD). Secara keseluruhan infeksi iridovirus ini dapat mengakibatkan infeksi yang sistemik pada ikan. Dikarenakan hubungan antara ketiga jenis Iridovirus ini tidak begitu jelas, makan penyakit Iridovirus tersebut diatas disajikan secara terpisah. Red Seabream Iridovirus Disease (RSIVD)
Penyakit ini merupakan infeksi iridovirus yang telah dikaji secara luas. Jenis virus ini sering ditemukan pada budidaya ikan Red Seabream di Jepang. Selanjutnya virus ini telah dilaporkan menginfeksi banyak jenis ikan Kerapu, seperti: Epinephelus akaara, E. malabaricus, E. coioides, E. awoara dan E. fuscoguttaus baik di Jepang, Taiwan, Thailand, Malaysia hingga ke Indonesia. Penyebab penyakit ini adalah Red Seabream Iridovirus Disease (RSIVD) yang memiliki ukran 130 – 196 nm. Umumnya menginfeksi ikan Kerapu atau ikan laut lainnya yang memiliki usia pertumbuhan kurang dari 1 tahun. Ikan yang terinfeksi oleh Red Seabream Iridovirus Disease (RSIVD) akan mengalami penurunan nafsu makan dan kematian terjadi pada 8 – 10 hari setelah ikan terpapar oleh virus.
Sleepy Grouper Disease (SGD) Agen penyebab penyakit ini memiliki ukuran 130 – 160 nm. Penyakit ini pertama kali dilaporkan terjadi pada ikan Kerapu Epinephelus tauvina ukuran 100 – 200 g dan 2 – 4 kg di Singapura dan Malaysia. Ikan yang terinfeksi akan menunjukkan gejala klinis luka yang akut, nafsu makan berkurang dan berenang baik sendirian atau mengapung di permukaan air atau tetap berada di dasar bak (Lio-Po Dan de la Pena, 2004).
Grouper Iridovirus Disease (GIVD) Agen penyebab penyakit ini adalah iridovirus dari genus Ranavirus yang memiliki ukuran 200 – 240 nm dan berbeda dari RSIVD. Ikan yang terinfeksi menunjukkan gejala klinis berenang yang tidak aktif, nafsu makan berkurang, letargik dan warna ekor dan sirip cenderung menjadi gelap. Ikan yang sudah terinfeksi virus ini secara akut akan mengapung ke permukaan kemudian akhirnya tenggelam ke dasar bak dan mati. Identifikasi virus dan penyakit viral memerlukan keahlian, pelatihan dan peralatan
khusus. Penyakit viral tidak dapat dikontrol dengan obat-obatan atau antibiotika karena virus menggunakan sel inangnya untuk proses reproduksi dan bertahan hidup. Dengan demikian pilihan terbaik untuk menghindari terjadinya wabah penyakit viral ini adalah dengan menghindari kondisi media pemeliharaan menjadi lebih berat dan mencegah terjadinya infeksi sekunder yang akan memperparah wabah. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan penerapan manajemen pemeliharaan yang baik antara lain dengan meningkatkan kualitas air media pemeliharaan, perbaikan kualitas pakan, pengurangan padat tebar, sanitasi lingkungan, penerapan standar karantina bagi ikan yang menunjukkan gejala terserang penyakit atau dengan memusnahkan ikan yang sudah positif terinfeksi oleh penyakit viral ini. Aplikasi vaksin juga dapat dilakukan, namun fakta bahwa ikan bersifat poikilotermal, menjadikan respon imun terhadap vaksin tidak dapat diprediksi sehingga vaksinasi harus lebih sering dilakukan.
II.2 Penyakit Bakterial Bakteri merupakan organisme yang paling umum dijumpai di lingkungan akuatik serta memiliki keragaman morfologi, ekologi dan fisiologis yang cukup tinggi. Sebahagian besar bakteri patogen pada budidaya ikan laut memiliki sel berbentuk batang pendek dan bersifat gram negatif. Penyakit yang ditimbulkan umumnya menunjukkan gejala septikemia dan borok (Irianto, 2005). Adapun sebagian bakteri lainnya bervariasi antara lain memiliki sifat gram positif dan memiliki bentuk sel kokus atau batang. Austin dan Austin (1999) mengidentifikasi 13 kelompok bakteri yang terdiri dari 51 genus, merupakan penyebab utama penyakit infeksi bakterial pada ikan. Genus bakteri tersebut antara lain: Mycobacterium, Aeromonas, Flavobacterium, Pseudomonas dan Vibrio. Pengelompokan bakteri patogen penting pada budidaya ikan laut disajikan pada Tabel 1.
Agen Penyakit Inang ikan laut utama Ketersediaan vaksin
Diagnosa PCR
Gram negative Listonella anguillarum (formerly Vibrio anguillarum)
Vibriosis seabass, striped bass, eel, red seabream
+ +
Vibrio ordalii Vibriosis Salmonids + - Vibrio salmonicida Vibriosis Atlantic salmon, cod + - Vibrio vulnificus Vibriosis Eels. Seabass + + Moritella viscosa (formerly Vibrio viscosus) Winter ulcer Atlantic salmon + - Photobacterium damselae subsp. Piscicida (formerly Pasteurella piscicida)
Photobacteriosis (Pasteurellosis)
Seabream, seabass, sole, striped bass, yellowtail
+ +
Pasteurella skyensis Pasteurellosis Atlantic salmon - - Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida Furunculosis Salmonids turbot + + Tenacibaculum maritimum (formerly Flexibacter maritimus)
Flexibacteriosis seabass, gilthead and red seabream
+ +
Pseudomonas anguilliseptica Pseudomonadiasis “Winter disease”
Seabream, eel, turbot, ayu
+ +
Gram Positif Lactococcus garvieae (formerly Enterococcus seriolicida)
Streptococcosis or lactococcosis
Yellowtail, eel + +
Streptococcus iniae Streptococcosis Yellowtail, Seabass, Barramundi
+ +
Streptococcus parauberis Streptococcosis Turbot + + Streptococcus phocae Streptococcosis Atlantic salmon - - Renibacterium salmoninarum BKD Salmonids + + Mycobacterium marinum Mycobacteriosis Seabass, turbot, - + Piscirickettsia salmonis Piscirickettsiosis Salmonids + +
Tabel 1. Pengelompokan bakteri pada budidaya ikan laut (Sumber: Toranzo et al., 2005)
Agen penyebab Penyakit Ikan yang terinfeksi
Gram negatif
Vibrionaceae
Vibrio alginolyticus Vibriosis Greasy grouper ( Epinephelus coioides) European seabass (D. labrax) Seabream (Sparus aurata)
Listonella anguillarum Vibriosis Red seabream (Pagrus major) Horse mackerel (Trachurus japonicus)
Vibrio parahaemolyticus Vibriosis Golden snapper (Lutjanus johni) Seabream (S. aurata)
Photobacterium damsela Pasteurellosis Amberjack (S. dumerii) European seabass (D. labrax) Seabream (S. aurata)
Enterobacteriaceae
Edwardsiella tarda Edwardsiellosis Japanese flounder (P. olivaceus)
Cytophagaceae
Flexibacter maritimus Saltwater myxobacteriosis
Greasy grouper (E. coioides) Asian seabass (Lates calcarifer) Mangrove snapper (L. argentimaculatus)
Gram positif
Streptococcus sp Streptococcosis Greasy grouper (E. coioides) Amberjack (S. dumerii) European seabass (D. labrax) Asian seabass (Lates calcarifer)
Tabel 2. Penyakit bakteri pada budidaya ikan laut (Sumber: T.S Leong and A. colorni, 2002) Penyakit infeksi bakterial pada ikan memiliki waktu inkubasi, tingkat mortalitas dan tanda-tanda klinis yang bervariasi. Sebagian besar bakteri patogen ikan yang sudah diketahui, dapat ditumbuhkan pada media buatan di luar tubuh inang. Hal utama yang harus disediakan adalah media sintetis untuk pertumbuhan bakteri. Memang tidak ada satu teknik yang dapat digunakan secara umum untuk mengisolasi bakteri patogenik ikan, namun media pertumbuhan dasar untuk pertumbuhan bakteri laut dapat digunakan, diantaranya adalah Marine agar, TSA yang ditambah NaCl hingga 2%, BHIA atau variasi lainnya. Isolasi bakteri juga dapat dilakukan dengan menggunakan media selektif, antara lain dengan menggunakan TCBSA (Thiosulphate Citrate Bile-Salt Sucrose Agar). Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan diverifikasi dengan merujuk pada tabel jenis-jenis infeksi bakteri pada budidaya ikan laut (Tabel 1 dan 2), maka berikut disajikan jenis infeksi bakteri, morfologi dan dampak yang ditimbulkan akibat infeksi bakteri dimaksud pada budidaya ikan laut.
1. Infeksi Vibrio Menurut Irianto (2005), Vibrio digolongkan sebagai bakteri dengan sifat gram negatif,
berbentuk batang dan sebagian besar hidup di perairan laut dan payau. Secara umum, infeksi akibat Vibrio disebut sebagai Vibriosis, kadang dikenal pula sebagai Salt water furunculosis, red boil dan pike pest. Beberapa jenis Vibrio yang bersifat patogen yaitu dengan mengeluarkan toksin ganas dan seringkali menyebabkan kematian pada ikan dan invertebrata laut adalah Vibrio alginolyticus, V. damsela, V. charchariae, V.anguilarum, V. ordalli, V. cholerae, V. salmonicida, V. vulnificus, V. parahaemolyticus, V. pelagia, V. splendida, V. fischeri dan V. Harveyi.
Bakteri vibrio diketahui sebagai bakteri oportunistik dan merupakan bakteri yang sangat
ganas dan berbahaya pada budidaya ikan laut karena dapat bertindak sebagai patogen primer dan sekunder. Sebagai patogen primer bakteri masuk tubuh ikan melalui kontak langsung, sedangkan sebagai patogen sekunder bakteri menginfeksi ikan yang telah terserang penyakit lain, misalnya oleh parasit (Post, 1987). Penyakit yang disebabkan oleh vibrio juga merupakan masalah yang sangat serius dan umum menyerang ikan-ikan budidaya laut dan payau. Penularannya dapat melalui air atau kontak langsung antar ikan dan menyebar sangat cepat pada ikan-ikan yang dipelihara dengan kepadatan tinggi. Gejala klinis awal dari ikan yang terinfeksi penyakit ini adalah anorexia atau hilang nafsu makan yang disertai dengan warna tubuh menghitam (Tendencia dan Lavilla-Pitogo, 2004). Ikan yang terinfeksi juga akan mengalami kehilangan keseimbangan dan menunjukkan perilaku berenang yang tidak normal. Bakteri vibrio yang menginfeksi ikan laut pada stadia juvenil selain lemah dan berwarna kehitaman, juga akan merangsang produksi lendir yang berlebihan. Pada tingkat akut, sirip punggung dan sirip ekor gripis dengan permukaan kulit menghitam seperti terbakar (Schubert, 1987). 2. Infeksi Streptococcus
Streptococcus adalah bakteri spheris Gram positif yang yang termasuk dalam family
Streptococcaceae dengan karakteristik khas hadir berpasangan atau membentuk rantai selama pertumbuhannya. Beberapa kelompok Streptococcus adalah flora normal manusia. Streptococcus menghasilkan berbagai enzim dan substansi ekstraseluler. Streptococcus merupakan kelompok bakteri yang heterogen, dan tidak ada sistem yang dapat mengklasifikasikannya. Dua puluh spesies, termasuk Streptococcus pyogenes (Grup A), Streptococcus agalactie (Grup B), dan Enterococci (Grup D) memiliki ciri-ciri dengan kombinasi gambaran: (1) sifat pertumbuhan koloni, (2) pola hemolisis pada agar darah (α hemolisis, β hemolisis, atau tidak ada hemolisis), (3) komposisi antigenik pada substansi dinding sel grup-spesifik, dan (4) reaksi biokimia. Secara umum banyak anggota dari genus Streptococcus bersifat patogen baik kepada manusia maupun hewan dan beberapa diantaranya telah terbukti memiliki sifat zoonosis.
Penyakit yang juga dikenal sebagai red boil disease ini seringkali dikaitkan dengan infeksi Vibriosis dan saat pertama kali dilaporkan terjadi pada ikan Kerapu Epinephelus malabaricus dan E. bleekeri di Brunei Darussalam, Malaysia, Singapore dan Thailand (Tendencia dan Lavilla-Pitogo, 2004). Dampak yang ditimbulkan pada inang diantaranya adalah mata menonjol (Exophthalmus), terdapat bintik merah pada kulit yang semakin membesar dan akhirnya pecah, menimbulkan septikemia berat yang akut atau dalam bentuk kronik dengan serangan terbatas pada sistem saraf pusat. Septikemia kemungkinan disertai dengan hemoragik pada sirip, kulit dan permukaan serosal. Pada kondisi akut dapat membentuk borok pada permukaan tubuh yang memberi peluang kepada masuknya mikroorganisme patogen lain ke dalam tubuh ikan (Irianto, 2005).
Kasus infeksi Streptococcus terutama terjadi pada sistem budidaya resirkulasi tertutup,
dan kemungkinan besar terkait dengan padat tebar tinggi, malnutrisi, oksigen rendah, kehadiran parasit dan kualitas air yang buruk, khususnya terkait dengan kandungan nitrat tinggi dan fluktuasi suhu air yang ekstrim. Bakteri Streptococcus dapat dikultur di agar darah (bovine, opine atau lapine) dan tumbuh pada suhu antara 22 dan 370 C, yang akan menghasilkan koloni berwarna abu-abu dengan ukuran 1 sampai 2 mm selama periode kultur 48 jam. Strain yang bersifat patogen pada ikan laut umumnya bersifat α-hemolytic (Kusuda et al., 1976), β-hemolytic (Robinson dan Meyer, 1966), atau bersifat non-hemolytic (Plumb et al., 1974).
3. Infeksi Flexibacter
Flexibacter spp. merupakan bakteri berbentuk batang (umumnya memiliki panjang 1-3 µm
dan lebar 0,5 µm) dan bersifat gram negative. Bakteri ini tidak memiliki flagella dan bergerak dengan meluncur, oleh karena itu Flexibacter spp sering juga disebut sebagai bakteri meluncur. Gejala klinis yang umum ditimbulkan antara lain terjadinya peradangan kulit disertai dengan bintik-bintik putih pada sirip ekor dan selanjutnya meluas ke arah kepala. Sirip ekor dan sirip anal dapat mengalami erosi berat, dan kulit akan mengalami borok berwarna putih keruh atau kelabu. Pada umumnya, insang ikan yang terinfeksi akan mengalami kerusakan yang ditandai dengan nekrosis pada ujung distal lamellae insang dan dapat meluas ke seluruh lamellae insang.
4. Infeksi Pseudomonas
Pseudomonas merupakan bakteri berbentuk batang pendek, motil dengan flagella polar
dan bersifat gram negatif. Penyakit yang juga dikenal sebagai pseudomonad hemorrhagic septicemia ini dilaporkan pertama sekali terjadi pada budidaya ikan kerapu E. tauvina di Malaysia.
II.3 Penyakit Parasit Secara umum, parasit dapat didefinisikan sebagai organisma yang hidup pada organisme lain, yang disebut inang, dan mendapat keuntungan dari inang tersebut, sementara inang menderita kerugian. Metoda invasi parasit pada inang dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada jenis parasit. Ada jenis parasit yang menginvasi inang dengan cara kontak langsung, melalui rantai makanan, phoresis ataupun melalui penetrasi pada kulit inang. Beragam jenis parasit telah dilaporkan menjadi penyebab yang signifikan terhadap timbulnya penyakit pada budidaya ikan laut. Pada fase perbenihan dan pendederan, infeksi parasit umumnya disebabkan oleh protozoa, khususnya oleh ciliata (Cruz-Lacierda and Erazo-Pagador, 2004), sementara pada fase perbesaran infeksi parasit lebih beragam. Untuk memberikan pemahaman tentang jenis infeksi parasit pada beberapa tahapan produksi ikan laut, maka pada Tabel 3, 4 dan 5 disajikan jenis parasit, wilayah infeksi dan gejala klinis yang ditimbulkan secara komprehensif .
Tabel 3. Penyakit ikan yang disebabkan oleh parasit protozoa pada beberapa tahapan budidaya ikan laut di wilayah Asia Pasifik, Tingkat infeksi ditandai sebagai: +++ = parah; ++ = moderat; + = ringan; - = umum diamati (Sumber : Tak Seng et al., 2006)
Ikan baru BudidayaCiliata
Cryptocaryon irritans (white
spot)
Insang dan
permukaan tubuh
++ +++ +++ +++ Titik putih pada permukaan tubuh, lethargy, produksi
mukus yang berlebihan, exophthalmia, warna tubuh
menghitam, menggososkkan badan ke jaring
Trichodina spp Insang dan
permukaan tubuh
++ ++ + + Lethargy , nafsu makan hilang, insang rusak disertai dengan
produksi mukus yang berlebihan, menggososkkan badan ke
jaring, hyperplasia dan neksrosis pada lapisan epidermis
Brooklynella spp Insang dan
permukaan tubuh
+++ +++ ++ + Lethargy, nafsu makan hilang, menggosokkan badan ke
jaring, Subcutaneous haemorrhage
Henneguya spp Insang dan
permukaan tubuh
+++ +++ ++ + Insang rusak dan hyperplasia
Dinoflagellata
Amyloodinium ocellatum Insang dan
permukaan tubuh
+++ +++ ++ + Ikan bergerak ke permukaan atau di titik aerasi, pergerakan
operculum insang cepat dan insang mengalami kerusakan,
tubuh menghitam, peningkatan produksi mucus yang
berlebihan di insang
Myxosporea
Spaerospora epinepheli Ginjal, hati, limpa
dan saluran
pencernaan
- ++ ++ + Hilang keseimbangan, mengapung dengan posisi terbalik,
beberapa disertai dengan perut membengkak, luka pada
mulut dan permukaan tubuh
Glugea spp Organ dalam - + ++ +++ Perut membengkak, terdapat nodul hitam pada organ
dalam
Pleistophora spp Organ dalam - + ++ +++ Perut membengkak, terdapat nodul hitam pada organ
dalam
Mikrosporidia
Parasit Wilayah infeksi Hatchery NurseryPerbesaran
Gejala klinis
Ikan baru KJA
Caligus spp (Sea lice) + + +
Pseudocaligus spp + + +
Lernanthropus latis + + +
Rhexanella sp ++ ++ +
Nerocila sp. ++ ++ +
Zeylanicobdella
arugamensis Permukaan
tubuh
+ + + Tidak ada gejala visual yang jelas, ikan yang terinfeksi akan berenang ke
permukaan untuk mendapatkan oksigen, pembelahan lamella insang
dan hyperlasia
Insang
Mengalami Lethargy dipermukaan air, hemorhagik, penggerusan sisik
dan kulit pada permukaan tubuh yang terinfeksi, hilang nafsu makan,
insang rusak dan produksi mucus yang berlebihan, haemolysis,
hyperanaemia dan hyperplasia
Microcotylid monogenea
Insang
Hilang nafsu makan, menggosokkan tubuh pada benda di sisi jaring,
perilaku berenang yang tidak teratur, pergerakan operculum insang
cepat, nekrosis pada kulit dan filamen insang
Sanguinicolid degenea
Parasit Wilayah
infeksi
Nursery Perbesaran Gejala klinis
Copepoda
Tabel 4. Penyakit ikan yang disebabkan oleh plathyhelminthes pada beberapa tahapan budidaya ikan laut di wilayah Asia Pasifik. Data ini tidak menyertakan data di hatchery karna umum ditemukan. Tingkat infeksi ditandai sebagai: +++ = parah; ++ = moderat; + = ringan; - = umum diamati (Sumber : Tak Seng et al., 2006) Tabel 5 Penyakit ikan yang disebabkan oleh parasit Crustacea dan lintah pada beberapa tahapan budidaya ikan laut di wilayah Asia Pasifik. Data ini tidak menyertakan data di hatchery karna umum ditemukan. Tingkat infeksi ditandai sebagai: +++ = parah; ++ = moderat; + = ringan; - = umum diamati (Sumber : Tak Seng et al., 2006)
Ikan baru KJA
Benedenia spp. +++ +++ +++
Neobenedenia spp +++ +++ +++
Pseudorhahdosynochus spp ++ ++ +
Diplectanum spp + + +
Haliotrema spp +++ +++ +
Dactylogyrus spp + + +
Heterobothrium spp. +++ +++ +
Heteraxine heterocerca +++ +++ +
Microcotyle spp. ++ ++ +
Bivagina sp. ++ ++ +
Choricotyle sp. ++ ++ +
Cruoricola lates ++ ++ +
Pearsonellum corventum ++ ++ +
Cardicola sp. ++ ++ +
Paradeontacylix spp. ++ ++ +
Sistem sirkulasi
Tidak ada gejala visual yang jelas, ikan yang terinfeksi akan
berenang ke permukaan untuk mendapatkan oksigen,
pembelahan lamella insang dan hyperlasia
Insang
Menggosokkan badan ke jaring, mengalami kerusakan pada
sisik di bagian kepala (diatas mata), insang rusak, lethargy,
hilang nafsu makan, produksi mukus yang berlebihan
Microcotylid monogenea
Insang
Tidak menunjukkan gejala khusus kecuali Lethargy, hilang
nafsu makan, insang rusak dan anemia
Sanguinicolid degenea
Insang dan permukaan
tubuh
Tubuh menghitam, perilaku berenang tidak normal,
menggosokkan badan ke jarring, insang rusak, lethargy dan
hilang nafsu makan, mata membengkak, hemoragik dan
nekrosis pada permukaan tubuh
Diplectanid monogenea
insang
Tubuh menghitam, menggosokkan badan ke jaring, insang
rusak, lethargy, hilang nafsu makan, produksi mukus yang
berlebihan
Dactylogyrid monogenea
Parasit Wilayah infeksi Nursery Perbesaran Gejala klinis
Capsalid monogenea
Bagian ini akan sedikit mengulas parasit utama yang umum ditemukan dan dilaporkan pada budidaya ikan laut di Indonesia termasuk infeksi yang disebabkan oleh parasit protozoik, yang meliputi: Dinoflagellata, Trichodina sp, Cryptocaryon irritans dan kelompok Mikrosporidia, serta yang disebabkan oleh parasit non-protozoik, yang meliputi: Trematoda monogenea, Trematoda digenea, Nematoda, Cespoda, dan Annelida. II.3.1 Infeksi yang disebabkan oleh parasit protozoa Pada dasarnya protozoa hidup bebas dan bersifat saprofitik, dan hanya pada kondisi tertentu menjadi bersifat parasit. Protozoa dapat bersifat sebagai parasit eksternal maupun internal dan dapat menggandakan diri baik di luar maupun di dalam tubuh inangnya. Parasit protozoa utama pada budidaya ikan laut diantaranya adalah: dinoflagellata, ciliata, myxosporea dan Mikrosporidia. II.3.1.1 Dinoflagellata Dinoflagellata merupakan protozoa dengan ukuran tubuh berdiamater hingga 100 µm dan mengandung khromatofor serta satu nukleus tepi. Pada saat berenang bebas, diameter tubuhnya hanya 20 µm dan dikenal luas sebagai agensia penyakit beludru atau penyakit koral (velvet disease). Spesies Dinoflagellata yang diketahui berperan sebagai patogen oportunis pada budidaya ikan laut adalah Amyloodinium ocellatum yang menyebabkan penyakit bintik putih di permukaan tubuh dan insang. Ikan yang terinfeksi menunjukkan gejala klinis diantaranya dengan sekresi lendir yang berlebihan, menempelkan tubuhnya dan memiliki perilaku berenang yang tidak normal. Ikan yang terinfeksi juga selalu berkumpul di permukaan air atau di dekat sumber aerasi, penggelapan warna tubuh dan peningkatan tingkat respirasi.
Gambar 2. Ikan kerapu bebek Cromileptes altivelis dengan insang rusak yang disebabkan
oleh Amyloodinium ocellatum (Gambar dari Zafran et al., 2000).
II.3.1.2 Trichodina sp Trichodina yang merupakan penyebab penyakit trikhodiniasis adalah protozoa dari kelompok ciliata yang memiliki bulu getar peritrikha dan bentuk bundar seperti cawan dengan diameter 50 µm. Bulu getar yang dimiliki terangkai pada kedua sisi sel, dan memiliki makro serta mikronukleus. Infeksi yang disebabkan oleh parasit ini sangat umum ditemukan pada budidaya ikan laut sistem intensif dan telah dilaporkan terjadi pada budidaya ikan kerapu Epinephelus bleekeri, E. tauvina, E. malabaricus, E. suillus dan Cromileptes altivelis di Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia dan Thailand (Cruz-Lacierda dan Erazo Pagador, 2004). Ikan yang terinfeksi akan menunjukkan gejala produksi mukus yang berlebihan, borok pada kulit, sirip rusak dan gangguan pernafasan pada insang. Pada skala berat, dapat terjadi hyperplasia sekunder dan hipertropi epitel pada insang. Penularan infeksi penyakit ini dapat dengan mudah terjadi melalui kontak langsung dengan ikan atau melalui air yang tekontaminasi. II.3.1.3 Cryptocaryon irritans Cryptocaryon irritans merupakan penyebab penyakit Cryptocaryonosis atau dikenal juga dengan penyakit bintik putih dikarenakan keberadaan beberapa atau sejumlah titik putih atau keabu-abuan pada permukaan tubuh dan insang pada ikan yang terinfeksi. Penyakit ini disebabkan oleh ciliate yang bergerak (motile ciliates) dan telah dilaporkan menginfeksi beberapa komoditas budidaya ikan laut di Indonesia, khususnya pada budidaya ikan kerapu Epinephelus bontoides, E. coioides, E. malabaricus, E. tauvina dan Cromileptes altivelis. Gejala umum yang ditunjukkan oleh ikan yang terinfeksi oleh parasit ini diantaranya adalah hilangnya nafsu makan, hemorhagi pada permukaan tubuh, mata exophthalmia dan perilaku berenang yang tidak normal. Ikan yang terinfeksi berat menunjukkan tingkat respirasi yang cepat, memproduksi mukus yang berlebihan dan menggosokkan badannya ke objek. Erosi pada kulit akan menghasilkan luka yang sangat rentan terhadap terjadinya infeksi sekunder (Cruz-Lacierda dan Erazo-Pagador, 2004). II.3.1.4 Mikrosporidia Parasit-parasit dari kelompok Mikrosporidia memiliki ciri khas yaitu membentuk kista pada berbagai organ inang. Kista yang terbentuk mengandung spora-spora kecil yang berukuran 1 – 2 µm. Diantara kelompok Mikrosporidia, yang termasuk kedalam parasit ikan dan mengancam keberlanjutan produksi budidaya ikan laut adalah Glugea sp yang dapat menyebabkan hipertrofi (hypertrophy) dan Pleistophora sp yang tidak menyebabkan hipertrofi. Parasit Glugea sp umumnya menginfeksi makrofag dan jaringan mesenkim dan selanjutnya menyebabkan hipertrofi dan berakibat pada deformitas organ-organ dalam seperti: hati, saluran pencernaan dan ovarium. Sementara Pleistophora hyphessobryconis umum ditemukan pada ikan hias dengan cara menginfeksi sarkoplasma serabut-serabut otot sehingga menyebabkan serabut-serabut tersebut terisi oleh kista Pleistophora. Pada infeksi tersebut tidak terjadi hipertrofi atau reaksi inflamasi di sekitar kista (Irianto, 2005)
II.3.1 Infeksi yang disebabkan oleh parasit non-protozoa Agensia parasit non-protozoik meliputi beragam hewan antara lain dari fila Platyhelminthes, Aschelminthes, Acanthocephala, Annelida dan Arthropoda. Parasit pada golongan non-protozoa ini sangat beragam dari sisi morfologi, sifat, inang yang diinfeksi dan organ atau jaringan yang menjadi sasaran infeksi. Untuk ikan yang hidup bebas di alam, infeksi parasit non-protozoik umumnya bersifat laten atau kronis. Sementara pada ikan budidaya, walaupun akibat yang ditimbulkan sama, namun karena kondisi lingkungan pemeliharaan yang dilakukan dengan tingkat kepadatan tinggi menyebabkan parasit ini dapat lebih mudah menyebar ke seluruh populasi ikan sehingga pada akhirnya akan memungkinkan populasi mengalami infeksi sekunder baik yang disebabkan oleh bakteri, fungi maupun virus. Pada bagian ini akan dibahas parasit non-protozoa yang umum ditemukan pada budidaya ikan laut di Indonesia, diantaranya: infeksi Benedenia, Neobenedenia, Diplectanum dan Haliotrema untuk kelompok Trematoda monogenea (Jhonny et al., 2002), Caligus spp dan Rhexanella sp untuk golongan crustacean dan Microcotylid monogenea (Novriadi et al, 2014) dan Lintah (leeches, Hirudinea) dari golongan Annelida (Novriadi et al., 2014) II.3.2.1 Trematoda monogenea Trematoda monogenea merupakan parasit yang biasa disebut dengan cacing pipih. Monogenea umumnya menginfeksi insang, kulit dan sirip ikan dengan beberapa spesies diantaranya bahkan dapat menginfeksi rektum, uretra, rongga tubuh bahkan saluran pembuluh darah (Irianto, 2005). Sebagian besar Trematoda monogenea bergerak dipermukaan tubuh inang dan memakan remah-remah bahan organik pada mukus kulit dan insang. Bagian anterior monogenea yang dilengkapi dengan kait memungkinkan parasit ini melekat pada inang sambil mengambil makanan dari tubuh inang. Tanda-tanda klinis yang ditimbulkan oleh infeksi parasit ini yaitu ikan menjadi letargik, berenang dekat permukaan air, bersembunyi pada salah satu sudut kolam pemeliharaan dan kehilangan nafsu makan. Kulit ikan yang terinfeksi oleh golongan Trematoda monogenea akan mengalami rontok sisik, luka dan mengeluarkan cairan kemerahan. Kondisi ini membuat ikan yang terinfeksi menjadi rentan terhadap infeksi sekunder oleh bakteri dan fungi. Infestasi berat akan menyebabkan gangguan pernafasan, insang bengkak dan pucat, laju pernafasan meningkat dan menjadi sensitif terhadap kandungan oksigen terlarut yang rendah. Dengan kondisi demikian, seringkali terlihat bahwa ikan yang terinfeksi akan muncul di permukaan air untuk mendapatkan oksigen, terutama pada ikan yang telah terinfeksi berat oleh parasit ini. Diplectanum
Parasit Diplectanum merupakan parasit Trematoda monogenea yang dapat
menyebabkan tingkat kematian serius dan sering ditemukan pada budidaya ikan laut. Parasit Diplectanum mempunyai kekhasan yang membedakannya dari spesies lain dalam Ordo Dactylogyridea yaitu mempunyai squamodisc (satu di ventral dan satu di dorsal), dan sepasang jangkar yang terletak berjauhan (Zafran et al., 1997). Parasit Diplectanum adalah parasit yang hidup pada insang ikan. Ikan laut yang terinfeksi oleh Diplectanum akan memeperlihatkan laju pernafasan yang lebih cepat dengan tutup insang yang selalu terbuka. Infeksi Diplectanum
mempunyai hubungan erat dengan penyakit sistemik seperti vibriosis. Insang yang terinfeksi biasanya berwarna pucat dan produksi lendirnya berlebihan (Chong & Chao, 1986). Ikan yang terinfeksi oleh parasit ini memperlihatkan gejala klinis, diantaranya adalah menurunnya nafsu makan, tingkah laku berenang yang abnormal pada permukaan air dan warna tubuh berubah menjadi pucat.
Gambar 3. Parasit Diplectanum (Foto: Balai Perikanan Budidaya Laut Batam) Benedenia
Parasit Benedenia merupakan parasit umum yang menginfeksi komoditas budidaya ikan
laut baik pada tahapan pendederan, perbesaran hingga pada tahapan calon induk dan induk. Parasit ini dapat menempel pada mata, permukaan tubuh dan insang ikan (Cruz-Lacierda dan Erazo-Pagador, 2004) sehingga menyebabkan ikan yang terinfeksi selalu terlihat menggosok-gosokkan badannya kepada objek sekitar dan berkumpul di dekat sumber aerasi dengan perilaku berenang yang tidak teratur. Parasit ini dapat menyebabkan kebutaan bila menempel pada mata dan luka pada kulit yang menyebabkan ikan rentan terhadap infeksi sekunder.
Gambar 4. Parasit Benedenia spp yang diambil dari permukaan tubuh ikan kerapu, a)
tahapan larva dan b) tahapan dewasa (Sumber foto: Cruz-Lacierda dan Erazo-Pagador, 2004).
Haliotrema spp
Parasit Haliotrema spp atau sering disebut cacing insang, merupakan parasit yang cukup berbahaya dan sering ditemukan pada budidaya ikan laut. Seperti parasit Diplectanum, parasit ini juga diidentifikasi dari preparat segar insang secara mikroskopis menggunakan mikroskop. Parasit ini dapat diidentifikasikan berdasarkan bentuk karakteristik morfologinya. Menurut laporan Zafran et al., (1998) parasit ini menjadi salah satu penyebab kematian massal pada ikan kerapu bebek Cromileptes altivelis. Ikan yang terinfeksi memperlihatkan gejala klinis; menurunnya nafsu makan, tingkah laku berenang yang abnormal pada permukaan air, warna tubuh berubah menjadi pucat. Serangan berat dari parasit ini dapat merusak filamen insang dan kadang-kadang dapat menimbulkan kematian karena adanya gangguan pernafasan.
Gambar 5. Parasit Haliotrema spp (sumber foto: Tak Seng et al., 2006)
II.3.2.2 Crustacea
Parasit dari golongan crustacean umumnya adalah kelompok copepod dan sering
dijumpai pada insang, tubuh maupun sirip ikan laut. Parasit crustacea tidak membutuhkan inang perantara untuk proses penyebaran penyakit dan mengalami proses moulting beberapa kali dari satu tahapan ke tahapan yang lain sebelum melakukan metamorphosis di tubuh inang yang sesuai. Jumlah parasit crustacean yang dilaporkan keberadaannya pada budidaya ikan laut sangat sedikit dan dilaporkan pada Tabel 5. Diantara parasit Crustacea tersebut, jenis yang utama menginfeksi komoditas budidaya ikan laut adalah Caligus spp.
Gambar 5. Parasit Caligus spp. (Foto: Balai Perikanan Budidaya Laut Batam)
Parasit Crustacea Inang
Aega sp Lates calcarifer; Chanos chanos
Argulus scutiformis Mugil cephalus; Takifugu rubripes
Caligus patulus Chanos chanos
Caligus sp Epinephelus sp; L. calcarifer, Lutjanus johnii
Ergasilus borneoensis Epinephelus coioides
Gnathia sp L. calcarifer; C. chanos; L. johni
Lemathropus latis Lates calcarifer
Lernaea cyprinacea Chanos chanos
Nerocila sp Epinephelus coioides; L. calcarifer Lutjanus johnii
Jassa sp Epinephelus coioides; L. calcarifer Lutjanus johnii
Microjassa sp Epinephelus coioides; L. calcarifer Lutjanus johnii
Lembos sp Epinephelus coioides; L. calcarifer Lutjanus johnii
Stenothole sp Epinephelus coioides; L. calcarifer Lutjanus johnii
Tabel 6. Jenis-jenis parasit crustacean yang ditemukan pada budidaya ikan laut di Asia Tenggara
(sumber: Woo et al., 2002) II.3.2.3 Annelida Diantara anggota annelida yang merupakan parasit bagi ikan adalah lintah (leeches, Hirudinea). Lintah dapat ditemukan baik pada ikan liar maupun budidaya. Lintah memiliki dua cakram penghisap (suckers) pada bagian anterior dan posterior. Umumnya lintah memiliki daur hidup langsung dan memiliki tingkat patogenitas yang beragam, tergantung kepada jumlah dan ukuran parasit, lama pelekatan dan hewan inangnya. Hewan inang yang terinfeksi berat akan menderita anemia kronik, ikan menjadi lemah dan memungkinkan terjadinya infeksi sekunder oleh fungi atau bakteri terutama pada daerah luka bekas pelekatan parasit. Diantara spesies lintah, Zeylanicobdella arugamensis merupakan jenis yang umum ditemukan pada budidaya ikan laut di Indonesia (Cruz-lacierda and Erazo-Pagador, 2004). Parasit berwarna coklat kehitaman ini menempel di beberapa bagian tubuh yang terinfeksi seperti di permukaan tubuh, sirip, mata, rongga pernafasan dan rongga mulut. Ikan yang terinfeksi parasit ini umumnya akan kehilangan nafsu makan, menunjukkan pergerakan yang lamban dan berenang di permukaan air.
II.4 Penyakit Mikosis Secara umum, fungi yang merupakan kelompok organisme berfilamen dan bersifat eukaryotic heterotrofik cenderung berkembang pada lingkungan yang bersifat asam dengan pertumbuhan optimal pada pH 4 – 6. Adapun kisaran suhu untuk pertumbuhan fungi adalah 5 – 400 C, beberapa diantaranya bersifat psikrofilik yang tumbuh optimum pada suhu dibawah 50 C dan lainnya bersifat termofilik yang mampu tumbuh hingga suhu 500 C atau lebih. Fungi memiliki habitat hidup yang tersebar luas yaitu tanah, air tawar maupun air laut (Irianto, 2005). Sejumlah fungi di perairan, umumnya bersifat saprofik, dimana fungi akan menjadi masalah bila ikan mengalami stress karna faktor lingkungan yang buruk, nutrisi yang buruk dan terdapat luka pada tubuh ikan. Kondisi tersebut akan menyebabkan ikan menjadi lemah atau jaringan menjadi rusak sehingga fungi dapat menginfeksi ikan.
Gambar 6. Lesi nodul berwarna putih atau granuloma diamati pada jaringan otot Cromileptes
altivelis (Foto dari Zafran et al., 1998)
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan Warintek. (2001), terdapat dua penyakit yang disebabkan oleh jamur pada budidaya ikan laut, yakni: Saprolegniasis dan Ichthyosporidosis. Infeksi Saprolegniasis disebabkan oleh fungi Saprolegni sp. Infeksi fungi ini menyebabkan perubahan warna pada kulit dan tumbuh jamur berwarna putih keabu-abuan yang makin lama akan semakin melebar dan pada akhirnya akan merusak otot ikan. Ikan yang terinfeksi sebaiknya dipisahkan dari koloni dan dimasukkan pada program karantina. Infeksi oleh fungi Saprolegnia sp ini jarang ditemukan terutama pada ikan yang memiliki sistem pertahanan tubuh kuat dan sehat. Penyakit mikosis lainnya adalah Ichthyosporidosis yang disebabkan oleh jamur Ichthyosporidium sp (Ichthyophonus sp). Jamur ini berkembang mengikis jaringan luar bagian kepala dan menyebabkan luka yang dalam yang berwarna kemerah-merahan dan dapat masuk ke dalam sampai ke bagian tengkorak kepala ikan. Kadang-kadang juga ditemukan di bawah kulit dan jaringan epitel kulit dari jaringan organ yang penting misalnya insang, usus, hati dan jantung dalam bentuk gumpalan granula. Keberadaan ichthyophoniosis di Indonesia telah dilaporkan terjadi pada budidaya ikan kerapu bebek Cromileptes altivelis (Catap and Lio-Po, 2004). Fungi ini diketahui telah menginfeksi sedikitnya 80 jenis ikan teleostei baik yang hidup di air tawar, laut maupun di lingkungan payau dan juga telah dilaporkan menginfeksi ikan yang hidup baik di zona tropis maupun zona dingin.
2012 2013 2012 2013 2012 2013
1 Teluk HurunTrematoda insang, Benedenia
sp, Trichodina sp
Trichodina sp, Benedenia sp,
Pseudorabdosynochus sp,
Oodinium sp, Cryptocaryon sp
Aeromonas sp,
Vibrio alginolitycus
V. vulnificus, Flexibacter sp,
V. damsela, V. carchariaeVNN ,Iridovirus VNN ,Iridovirus
2 Kalianda Trichodina sp negatif
Pseudomonas sp,
V.alginolitycus , V.
vulnificus,
Aeromonas sp
positif (tidak diidentifikasi) VNN ,Iridovirus VNN ,Iridovirus
3 TarahanCryptocaryon sp, Trematoda
insangnegatif
Pseudomonas sp,
Actinobacillus sppositif (tidak diidentifikasi) VNN ,Iridovirus VNN ,Iridovirus
4 Tanjung PutusTrichodina sp, Amyloodinium
sp
Haliothrema sp,
Pseudorabdosynochus sp,
Trichodina sp
positif (tidak
diidentifikasi)
V. damsela, Pseudomonas
sp, V. alginolyticusnegatif iridovirus
5 RinggungTrematoda insang, Benedenia
sp, Pseudorabdosynochus sp V. algonolitycus positif (tidak diidentifikasi) iridovirus iridovirus
6 Pulau Puhawang Trematoda insang Pseudorabdosynochus spV. alginolitycus, V.
parahaemolitycusFlexibacter sp, V. vulnificus negatif VNN
7 Pulau TegalTrematoda insang,
Cryptocaryon sp,
Benedenia sp,
Pseudorabdosynochus sp
positif (tidak
diidentifikasi)V. vulnificus VNN ,Iridovirus VNN ,Iridovirus
8 Padang Cermin negatif Trematoda insang negatif V. vulnificus negatif negatif
No Parasit Bakteri Virus
Patogen
Lokasi
III. Status Terkini Penyakit Ikan Air Laut di Indonesia
III.1 Jenis Penyakit
Data status terkini penyakit ikan air laut di Indonesia disajikan pada Tabel 7,8,9 dan 10 yang merupakan hasil pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan yang dilakukan oleh BBPBL Lampung, BPBL Lombok, BPBL Batam dan BPBL Ambon tahun 2012 – 2013.
Tabel 7. Distribusi penyakit pada budidaya ikan kerapu di Teluk Lampung Tahun 2012 – 2013 (Sumber: BBPBL Lampung)
Tabel 8. Distribusi penyakit pada budidaya ikan laut tahun 2012-2013 (Sumber: BPBL Lombok)
Parasit Bakteri Virus
1 Lombok timur Kerapu bebek negatif negatif VNN, Iridovirus
Dactylogyrus sp Vibrio anguillarum Iridovirus
Microsporidia V. parahaemolyticus negatif
Yersinia ruckerii negatif
negatif Vibrio anguillarum Iridovirus
V. parahaemolyticus negatif
Kakap putih negatif negatif Iridovirus
Bawal Bintang negatif negatif Iridovirus
Clown fish negatif Pseudomonas sp negatif
3 Lombok Utara Kerapu bebek negatif negatif Iridovirus
4 Sumbawa Barat Kerapu bebek negatif negatif Iridovirus
5 Bali Kerapu bebek negatif negatif negatif
6 NTT Kerapu bebek negatif negatif negatif
PatogenNo Lokasi Ikan yang terinfeksi
Lombok Barat2 Kerapu bebek
Kerapu macan
Tabel 9. Distribusi penyakit pada budidaya ikan laut tahun 2012-2013 (Sumber: BPBL Batam)
Tabel 10. Distribusi penyakit pada budidaya ikan laut tahun 2012-2013 (Sumber: BPBL Ambon)
Parasit Bakteri Virus
1 Tiaw Wang Kang Kerapu Cantang Diplectanum sp Vibrio sp VNN
2 Pulau Setengah Bawal Bintang Diplectanum sp Vibrio sp Iridovirus
3 Selat nenek Trichodina sp
Diplectanum sp
4 Sungai Boko Kerapu macan Diplectanum sp Vibrio sp VNN, Iridovirus
5 Selat nipah Kerapu Cantang Trichodina sp Vibrio sp negatif
Trichodina sp
Rhexanella sp
Hirudinea
Benedenia sp
Caligus sp
Cryptocaryon irritans
1 Langkat-Sumatera Utara Kerapu lumpur Cryptocaryon irritans Iridovirus
Trichodina sp
Benedenia sp
Trichodina sp Flexibacter sp
Cryptocaryon irritans Vibrio sp
Haliotrema spp
Caligus sp
Rhexanella sp
Hirudinea
Haliotrema spp
Caligus sp
Rhexanella sp
Hirudinea
4 Natuna Kerapu macan Benedenia sp Vibrio sp VNN
Benedenia sp
Hirudinea
Rhexanella sp
5 Lingga Kerapu macan Vibrio sp VNN
2
3
Karimun
Bintan
Bawal Bintang
Kakap Putih
Kerapu macan
Kakap putih
Vibrio sp negatif
VNN, IridovirusVibrio harveyi
Vibrio sp
Vibrio sp Iridovirus
VNN, Iridovirus
Kerapu macan
Vibrio sp
Iridovirus, VNN
No Lokasi Ikan yang terinfeksi
Kota Batam
Luar Batam
Kakap Putih
Patogen
7 Tanjung Riau
Kerapu macan negatif negatif
6Tanjung Piayu
Parasit Bakteri Virus
Benedenia sp Vibrio anguillarum Iridovirus
Trichodina sp Vibrio alginolyticus VNN
Cryptocaryon irritans Brooklynella sp
Vibrio fluvialis
Benedenia sp
Trichodina sp
Cryptocaryon irritans
Uronema sp
Haliotrema sp
Cryptocaryon irritans
Amyloodinium sp
Trichodina sp
Cryptocaryon irritans
Amyloodinium sp
6 Banggai cardinalfish Cryptocaryon irritans Vibrio sp negatif
7 Kakap putih negatif negatif Iridovirus
8 Bawal Bintang negatif negatif Iridovirus
Vibrio alginolyticus negatif
Vibrio parahaemolyticus negatif
negatif negatif
3
4
5
Kerapu cantang
Kerapu macan
Clown fish
Bubara
PatogenIkan yang terinfeksiNo
1 Kerapu bebek
2 Vibrio parahaemolyticus VNN
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa parasit Trichodina sp, Benedenia sp, Diplectanum sp dan Cryptocaryon irritans menunjukkan insidensi dengan intensitas cukup tinggi pada budidaya ikan laut untuk komoditas ikan Kerapu (Epinephelus sp), Kakap putih (Lates calcarifer), Bawal Bintang (Trachinotus blochii) hingga ikan hias clown fish (Amphiprion sp). Sementara infestasi Haliotrema sp, Amyloodinium sp, Uronema sp, Rhexanella sp, Pseudorabdosynochus sp dan caligus sp memiliki tingkat intensitas moderat. Selain infestasi parasit, kegiatan pemantauan juga mengidentifikasi keberadaan bakteri Vibrio alginolyticus, V. parahaemolyticus, V. fluvialis, V. vulnificus, V. damsela, V. anguillarum, V. harveyi, V. charchariae, Pseudomonas, Flexibacter sp, dan Yersinia ruckeri menjadi penyebab utama penyakit infeksi bakterial pada budidaya ikan laut. Kegiatan pemantauan juga menunjukkan bahwa infeksi nodavirus sebagai agen penyebab Viral Nervous Necrosis dan iridovirus telah diketahui menginfeksi hampir semua komoditas ikan laut penting di Indonesia. III.2 Analisis Resiko Analisis resiko didefinisikan sebagai sebuah media yang menyediakan informasi objektif, tertelusur dan menggunakan metoda yang didokumentasikan dengan baik bagi para pengambil kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap resiko yang ditimbulkan oleh tindakan atau keadaan tertentu (MacDiarmid, 1977). Analisis resiko akan berusaha untuk menjawab pertanyaan: (1) apa penyebab sebuah masalah?; (2) bagaimana bisa terjadi permasalahan tersebut?; (3) apa konsekuensi dari permasalahan tersebut?; dan (4) apa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi konsekuensi dari permasalahan tersebut. Analisis resiko untuk penyakit pada budidaya ikan laut selama ini tidak terlalu mendapatkan perhatian yang serius dari banyak negara produsen akuakultur dunia (Bondad-Reantaso et al., 2005). Hal ini sangat berbeda dengan perhatian yang diberikan untuk analisis resiko pada sektor perikanan lainnya seperti: (1) Analisis resiko import (IRA /Import Risk Analysis) untuk penyakit infeksius atau patogen; (2) Hazard analysis and critical control point (HACCP) untuk keamanan pangan dan kesehatan masyarakat dan (3) Geoinformatics/ pemetaan resiko untuk bencana alam. Kondisi ini tentu saja menjadi dorongan bagi para pengambil kebijakan mengingat saat ini penyakit ikan sudah dapat dikategorikan menjadi salah satu faktor yang memiliki resiko tinggi dikarenakan frekuensi kemunculan dan tingkat penyebarannya telah berdampak kepada banyak sektor, tidak hanya dalam hal ekonomi dan dampak sosial yang ditimbulkan, tetapi juga investasi yang harus disediakan oleh para pelaku usaha budidaya untuk tindakan pengendalian penyakit dan berbagai program pengembangan lainnya. Beberapa aspek pengelolaan resiko pada sektor budidaya perikanan disajikan pada Tabel 11.
Resiko / Bahaya Pengelolaan Resiko Resiko manajemen dan operasional Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)/ Best
Management Practices (seperti: good governance, Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Pengelolaan obat dan pakan, Pengelolaan panen dan transportasi ikan yang baik, pengelolaan KJA sistem cluster, Asuransi perikanan
Patogen/penyakit pada budidaya Import risk analysis; strategi nasional untuk penguatan kesehatan ikan, biosekuriti, monitoring dan surveillance hama penyakit ikan, Sistem deteksi dini, Pengelolaan Kesehatan Ikan yang Baik, Vaksinasi dan tindakan prophylactic lainnya
Resistensi terhadap anti-mikrobial Vaksinasi, Aplikasi sistem pemeliharaan ikan yang baik dengan mengurangi pemakaian antibiotika
Bencana alam Aquaculture Insurance, Geoinformatika Keamanan pangan dan kesehatan masyarakat
HACCP, Good Management Practices [good aqua-culture practices (GAP), good hygienic practices (GHP), good manufacturing practices (GMP)], Pengendalian keamanan pangan dan Edukasi untuk konsumen
Resiko/bahaya pekerjaan Meningkatkan pemahaman para pekerja tentang resiko/bahaya dan keamanan kerja; menggunakan pakaian pelindung, menyediakan alat pertolongan pertama di tiap unit kerja, pengukuran yang tertelusur dan lainnya
Resiko lingkungan Kebijakan yang pro-aktif terhadap lingkungan
Tabel 11. Contoh pengelolaan resiko pada sektor budidaya perikanan (Sumber: Bondad-Reantaso et al., 2005) Oleh karena itu, maka pada bagian ini akan dibahas analisa resiko dari keberadaan penyakit yang timbul pada budidaya ikan laut. III.2.1 Penyakit Viral Penyakit viral pada budidaya ikan laut di wilayah Asia Tenggara telah mengalami peningkatan sejak tahun 1980-an (Nakai et al, 1995; Bondad Reantoso, 2001) dan menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya peningkatan produksi. Tindakan pengendalian melalui pendekatan prophylactic merupakan salah satu kunci yang paling baik untuk dapat mencegah munculnya infeksi penyakit viral pada budidaya ikan laut. Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 7,8, 9, dan 10 tentang distribusi penyakit diketahui bahwa Nadaviridae sebagai agen penyebab penyakit Viral Nervous Necrosis dan Iridovirus menjadi penyebab utama penyakit viral pada budidaya ikan laut di Indonesia.
1. Viral Nervous Necrosis (VNN)
1.1 Penyebab. Piscine nodavirus dari genus Betanodavirus (25-30 nm) merupakan agen
penyebab utama penyakit VNN. Penyakit ini pertama kali dilaporkan keberadaannya pada ikan Japanese parrotfish (Oplegnathus fasciatus) pada saat terjadi wabah pada tahun 1985-1987 (Yoshikoshi and Inoue, 1990) dan saat ini keberadaan VNN telah teridentifikasi di hampir seluruh lingkungan untuk pengembangan budidaya ikan laut di wilayah tropis, utamanya pada fase benih (Leong T.S and A. Colorni, 2002).
1.2 Pemicu infeksi. Suhu memainkan peranan penting dalam proses replikasi dan
peningkatan sifat patogenitas dari Piscine nodavirus. Sebagai contoh: RGNNV yang diisolasi dari ikan kerapu menghasilkan efek cytopathic pada sel GF-1 pada suhu 24-320 C tetapi tidak pada suhu 200 C atau 370 C. Pada larva yang diuji tantang dengan RGNNV pada suhu 280C, kematian mencapai 100% pada 50-80 jam setelah inokulasi. Pada uji coba yang dilakukan di benih ikan kerapu E. akaara, RGNNV menyebabkan kematian hingga 100% pada suhu 24-280C, namun pada suhu 16 dan 200C, mortalitas berkurang hingga 57-61% dan munculnya perilaku berenang yang tidak normal dan kematian pada ikan dapat ditunda (Lio-PO dan De la Pena, 2004). Virus ini dapat ditularkan dari ikan sakit ke ikan sehat dalam kurun waktu 4 hari setelah terjadi kontak. Nodavirus dapat dideteksi pada ikan yang tidak menunjukkan adanya perilaku terkena infeksi, oleh karena itu, Induk ikan yang terinfeksi dapat menjadi wadah dan sumber penularan virus ke larva yang dihasilkan.
1.3 Dampak yang ditimbulkan. Tingkat serangan VNN (Viral Nervous Necrosis) yang
umumnya menyerang sistem organ syaraf mata dan otak (Yuasa et al., 2001) ini dilaporkan telah menyerang sebagian besar budidaya ikan kerapu di Indonesia dengan tingkat kematian hingga 100% (Putri et al., 2013). Bahkan Koesharyani et al. (2001) menjelaskan bahwa kematian akibat infeksi VNN ini dapat mencapai 100% pada stadia larva, namun tidak pada stadia juvenile dan fingerling (ikan muda). Data yang diterima dari BPBL Ambon menyebutkan bahwa infeksi VNN pada benih Kerapu bebek (Cromileptes altivelis) dengan ukuran 5-6 cm digolongkan sebagai infeksi dengan tingkat mortalitas < 30%, sementara pemantauan yang dilakukan di BPBL Batam menunjukkan bahwa infeksi VNN pada ikan Kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) dan Kakap putih (Lates calcarifer) pada stadia juvenile menyebabkan kematian hingga 70%. Gejala yang ditimbulkan oleh infeksi VNN ini menyebabkan ikan berputar-putar atau whirling, terjadi sleeping dead atau ikan berada di dasar seperti mati serta adanya gejala tingkah laku yang tidak wajar (Yuasa et al., 2000).
1.4 Tindakan Pengendalian. Induk yang bersifat carrier VNN telah diketahui menjadi
penyebab infeksi pada larva yang dihasilkan. Oleh karena itu Screening kesehatan induk dengan menggunakan teknik Polymerase Chain Reaction (PCR) menjadi sangat penting. Hanya induk yang dinyatakan bebas VNN yang diperbolehkan untuk melakukan pemijahan yang diikuti dengan proses desinfeksi atau fertilisasi telur dengan
menggunakan ozon atau iodine. Prosedur ini cukup efektif untuk mencegah penularan vertical dari virus ini.
Pengelolaan pemeliharaan ikan yang baik khususnya dipanti benih (hatchery) sangat penting dalam pengelolaan infeksi VNN. Betanodavirus cukup resistan terhadap beberapa parameter lingkungan, oleh karena itu sangat mungkin apabila virus dapat ditularkan melalui air yang tercemar. Sistem pemeliharaan dengan menggunakan air yang telah diolah secara fisik, biologi maupun kimia dan menggunakan sistem resirkulasi cukup efektif dalam mengurangi kemungkinan terinfeksi oleh VNN. Sebagai tambahan, introduksi benih yang telah memiliki sertifikat Specific Pathogen Free (SPF) dari panti benih yang telah memiliki sertifikat CPIB, penerapan Biosecurity dalam sistem produksi, penerapan proses karantina terhadap ikan introduksi serta aplikasi sistem pemeliharaan yang memperhatikan carrying capacity untuk menghindari kondisi stress pada ikan juga sangat efektif dalam mengurangi kemungkinan timbulnya wabah penyakit.
Pada fase benih, aplikasi vaksinasi cukup efektif dalam meningkatkan sistem pertahanan tubuh baik sistem imun spesifik maupun adaptif pada ikan. Tindakan vaksinasi akan merangsang pembentukan antibodi spesifik dan menghasilkan perlindungan yang kuat bagi ikan dari infeksi virus VNN. Sebagai tambahan, sejak suhu memainkan peranan penting dalam menginduksi penggandaan virus, maka penerapan manipulasi suhu cukup penting untuk mengurangi kemungkinan timbulnya wabah penyakit.
2. Iridovirus 2.1 Penyebab. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang termasuk ke dalam family Iridoviridae
dan memiliki bentuk heksagonal dengan diameter 200-240 nm (pada ikan red seabream) dan 140-160 nm (pada ikan kerapu) (Danayadol et al., 1997; Kasornchandra and Khongpradit, 1997). Infeksi virus ini dilaporkan telah menyebar di lingkungan budidaya di wilayah Asia Tenggara (T.S Leong and A. Colorni, 2002) dan menjadi salah satu penyakit dalam daftar OIE di tahun 2014. Di Indonesia, Infeksi Iridovirus pertama kali terdeteksi di lokasi budidaya kerapu di Sumatera Utara (Rukyani et al., 1993) dan kemudian menyebar di unit-unit perbenihan yang ada di Lamongan, Jawa Timur (Mahardika et al., 2002). Data terkini menunjukkan bahwa infeksi Iridovirus ini telah menyerang budidaya ikan Kerapu di Lampung, Pulau Seribu (Trobos, 2011), Batam (Romi et al, 2014) dan Ambon.
2.2 Pemicu infeksi. Lingkungan yang terkontaminasi dan kualitas air yang buruk memicu
peningkatan infeksi iridovirus. Hal ini utamanya disebabkan oleh kontak langsung antara insang dan saluran pencernaan ikan dengan lingkungan. Penyebaran virus antara ikan yang berada di sistem produksi yang sama akan terjadi dengan sangat cepat bila ikan tidak memiliki sistem imun yang baik dan berada dalam kondisi lemah. Naum, belum ada laporan yang menyatakan bahwa virus ini dapat menyebar secara vertical, karena pada umumnya virus ini menyebar akibat introduksi ikan impor yang telah terinfeksi oleh Iridovirus sebelumnya atau bersifat carier terhadap Iridovirus (Lio-Po and de la Pena, 2004).
2.3 Dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan data pemantauan yang dilakukan oleh BPBL
Ambon diketahui bahwa tingkat serangan infeksi Iridovirus telah menyebabkan tingkat mortalitas < 30% pada induk Kerapu bebek dan Kakap putih. Sementara pada stadia benih, infeksi Iridovirus menyebabkan tingkat mortalitas hingga 60%, khususnya untuk komoditas Bawal bintang (Trachinotus blochii) dan Kerapu bebek (C. altivelis). Menarik untuk diamati bahwa Bawal bintang saat ini cukup rentan terhadap infeksi Iridovirus. Pengamatan yang dilakukan di BPBL Batam bahkan menunjukkan bahwa infeksi Iridovirus ini telah mulai diamati keradaannya mulai dari stadia telur, larva, benih hingga perbesaran dengan tingkat mortalitas Trachinotus blochii mencapai 40 – 60%. Infeksi Iridovirus sangat menarik untuk diamati karena terdapat pola infeksi yang bersifat host specific. Hal ini terbukti dari investigasi yang dilakukan oleh tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya (P4B) di sentra produksi ikan Kerapu di Teluk Mandeh Sumatera Barat yang mengungkapkan fakta bahwa tingkat mortalitas tinggi hingga mencapai 100% hanya terjadi pada ikan Kerapu bebek (C. altivelis) sementara ikan kuwe yang juga dipelihara di Keramba tidak terinfeksi oleh Iridovirus (INFHEM, 2013).
2.4 Tindakan pengendalian. Penerapan sistem karantina ikan terhadap ikan baru atau
introduksi menjadi hal yang harus dilakukan mengingat penyebaran utama virus ini terjadi akibat aktivitas impor ikan dari unit produksi yang tidak memiliki sertifikat (Lio-PO and de la Pena, 2004). Sebagai tambahan, aplikasi Biosecurity, penerapan Good management practices (GMPs) pada sistem budidaya serta mengurangi tingkat stress pada ikan selama masa pemeliharaan dapat menjadi strategi untuk menghindari timbulnya wabah Iridovirus.
Sebuah uji coba yang dilakukan oleh Nakajima et al., (1997) menunjukkan bahwa aplikasi
vaksinasi menghasilkan tingkat kelulushidupan yang lebih baik dibandingkan control. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan sistem kekebalan tubuh menjadi tahapan penting untuk menghadapi infeksi penyakit viral. Tindakan Prophylactic lainnya seperti aplikasi Immunostimulan, probiotik, vitamin dan mineral yang bertujuan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan kesehatan ikan merupakan tindakan pengendalian terbaik yang dapat diterapkan pada sistem budidaya ikan laut.
III.2.2 Penyakit Bakterial
Berdasarkan hasil pemantauan, dapat diidentifikasi bahwa infeksi Vibriosis (yang disebabkan oleh: Vibrio alginolyticus, V. parahaemolyticus, V. fluvialis, V. vulnificus, V. damsela dan V. anguillarum), Infeksi Pseudomonas, Flexibacter sp, dan Yersinia ruckeri menjadi penyebab utama penyakit bakterial pada budidaya ikan laut di Indonesia.
1. Infeksi Vibriosis
1.1 Penyebab. Berdasarkan data, Infeksi Vibriosis setidaknya disebabkan oleh delapan spesies, yaitu: 1) Vibrio anguillarum (spesies yang paling umum diisolasi dari ikan laut) 2) Vibrio alginolyticus (dilaporkan telah menginfeksi beberapa jenis ikan seperti: ikan
kerapu Grouper spp dan Kakap putih Lates calcarifer 3) Vibrio parahaemolyticus (dilaporkan telah menginfeksi Ikan Kerapu Grouper spp dan
clown fish 4) Vibrio fluvialis (dilaporkan pada ikan Kerapu bebek Cromileptes altivelis) 5) Vibrio vulnificus (dilaporkan menyebabkan infeksi pada ikan Kerapu Epinephelus spp 6) Vibrio damsela (dilaporkan menginfeksi ikan Kerapu Epinephelus spp) 7) Vibrio carchariae (dilaporkan menginfeksi ikan Kerapu Epinephelus spp) 8) Vibrio harveyi (dilaporkan menginfeksi ikan Kerapu Epinephelus spp) Kajian lebih lanjut menunjukkan bahwa cytotoxins yang diproduksi oleh Vibrio spp mampu menembus hingga mukus dan melakukan penetrasi hingga lapisan mukus dan menyebabkan keusakan pada kulit ikan (Krovacek et al., 1987).
1.2 Pemicu infeksi. Pada dasarnya Vibrio merupakan jasad oportunistik (Defoirdt et al.,
2005). Berlangsungnya wabah Vibriosis dapat terjadi akibat stress lingkungan yang menjadikan kondisi ikan lemah atau diinduksi oleh adanya infeksi primer yang disebabkan oleh parasit sehingga menyebabkan kerusakan jaringan pada ikan dan menjadi situs yang menguntungkan bagi Vibrio spp untuk memulai infeksi. Infeksi Vibriosis kemungkinan besar dapat ditularkan melalui mulut (oral transmission), baik yang berasal dari pakan (rucah) ataupun lingkungan. Hal ini didukung oleh bukti bahwa Vibrio spp dapat diisolasi dari saluran pencernaan ikan yang secara klinis dinyatakan sehat (Irianto, 2005). Infeksi Vibriosis juga dapat disebabkan oleh adanya luka akibat penanganan yang kurang baik pada saat grading, handling dan transportasi. Faktor lingkungan juga dapat memicu timbulnya wabah penyakit ini seperti disebabkan oleh faktor suhu yang tinggi, variasi tekanan osmotik dan polusi yang disertai dengan partikel organik (Pedersen and Larsen, 1998). Pada keadaan tertentu, Vibrio dapat menembus dinding intestinum dan menyebabkan infeksi sistemik. Ketika terjadi wabah, populasi Vibrio dilingkungan akan meningkat pesat sehingga memperbesar kemungkinan untuk menginfeksi organism akuatik lainnya.
1.3 Dampak yang ditimbulkan. Secara umum, infeksi Vibriosis dapat menyebabkan
mortalitas > 50% pada ikan budidaya. Dalam keadaan tertentu, terutama apabila padat tebarannya tinggi, seringkali menyebabkan mortalitas hingga 100 % (Irianto, 2005). Kondisi ini menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup tinggi bagi para pembudidaya ikan.
I.4 Tindakan pengendalian. Pendekatan Prophylaksis, diantaranya melalui pemberian immunostimulan, vaksinasi dan probiotik saat ini lebih diutamakan dibandingkan dengan penggunaan antibiotika dan bahan kimia lainnya. Hal ini utamanya disebabkan oleh penggunaan massive dari antibiotika telah menyebabkan resistensi pada bakteri target maupun bakteri non-target terhadap senyawa antibiotika, sehingga pengobatan manjadi tidak efektif. Penggunaan antibiotika juga memiliki dampak tersendiri berupa alergi pada manusia yang mengkonsumsi produk akhir dari aktivitas budidaya dengan kandungan residu antibiotika didalamnya (Cabello, 2006).
Sejumlah vaksin untuk mengatasi infeksi Vibriosis sudah tersedia, mulai dari vaksin
polyvalen hingga kepada vaksin spesifik untuk mengatasi wabah Vibrio spp tertentu pada sistem pemeliharaan. Aplikasi immunostimulan juga dapat menjadi strategi alternatif terbaik untuk ikan budidaya, dimana dengan pemberian immunostimulan diharapkan sistem kekebalan tubuh ikan, baik sistem imun spesifik maupun non-spesifik, meningkat dan berguna untuk melawan infeksi bakteri patogen. Selain tindakan tersebut, aplikasi probiotik untuk melancarkan sistem pencernaan ikan dan memperbaiki kualitas air hingga kepada penerapan quorum sensing untuk menghambat komunikasi antar bakteri dapat menjadi pilihan untuk tindakan pengendalian infeksi vibriosis.
2. Infeksi Pseudomonas 2.1 Penyebab. Infeksi ini utamanya disebabkan oleh Pseudomonas sp dan berdampak pada
budidaya ikan Kerapu (Epinephelus spp) 2.2 Pemicu infeksi. Pseudomonas sp menginfeksi ikan ketika inang mengalami stress akibat
kondisi lingkungan seperti perubahan suhu air yang tinggi, pada tebar tinggi, kualitas air yang buruk dan asupan nutrisi yang kurang (Tendencia and Lavilla-Pitogo, 2004).
2.3 Dampak yang ditimbulkan. Dua puluh hingga enam puluh persen tingkat mortalitas dapat
diamati pada populasi ikan yang terinfeksi. Umumnya ikan yang terinfeksi memiliki gejala klinis seperti hemoragik septicemia, hemoragik pada insang dan ekor dan borok pada kulit.
2.4 Tindakan pengendalian. Hindari faktor-faktor pemicu timbulnya wabah seperti perubahan
suhu yang ekstrim, kepadatan tinggi, kualitas air buruk dan asupan gizi buruk untuk mencegah terjadinya infeksi Pseudomonas. Tindakan pengendalian yng efektif adalah selain melakukan tindakan Prophylaksis (Vaksinasi, Immunostimulan, Probiotik dan Vitamin), lakukan pemindahan ikan-ikan yang terinfeksi secara rutin ke dalam bak yang berisikan air bak dan sudah disterilisasi.
3. Infeksi Flexibacter sp.
3.1 Penyebab. Bakteri gram negative Flexibacter maritimus (baca: Tenacibaculum maritinum), dengan bentuk batang dan memiliki panjang 1-3 µm. Bakteri ini tidak memiliki flagella dan bergerak dengan meluncur.
3.2 Pemicu infeksi. Infeksi F. maritimus seringkali dipicu oleh kondisi stress yang umumnya
ditimbulkan oleh suhu air yang tinggi (25-32⁰ C), padat tebar tinggi, luka dan kualitas air buruk (kandungan oksigen terlarut rendah dan konsentrasi ammonia bebas meningkat).
3.3 Dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan data distribusi penyakit, infeksi Flexibacter sp ini
ditemukan pada komoditas Kakap putih dengan tingkat mortalitas hingga 30 %. Publikasi yang dilakukan oleh Gibson-Kueh (2012) menyatakan bahwa infeksi Flexibacter spp pada ikan kakap putih yang berasosiasi dengan penyakit sistemik lainnya dapat menyebabkan tingkat mortalitas hingga lebih dari 50%. Pada ikan kerapu, tingkat mortalitas bahkan dapat mencapai hingga 80% dalam beberapa hari jika ikan tidak diobati. Bakteri ini dapat menghancurkan wilayah ekor ikan dalam waktu dua hari.
3.4 Tindakan Pengendalian. Untuk tahap pencegahan, hindari penanganan ikan yang kasar
untuk meminimalisasi terjadinya luka yang dapat menjadi portal bagi masuknya infeksi bakteri dikarenakan adanya kerusakan fisik. Selalu impor benih ikan yang telah memiliki Health certificate dan dari panti benih yang bersertifikat CPIB. Tahapan pencegahan lainnya dapat dilakukan dengan memperkuat sistem imun ikan melalui pemberian immunostimulan serta meningkatkan kualitas air media pemeliharaan. Tindakan pengendalian dapat dilakukan dengan perendaman air tawar selama 10-15 menit dan perendaman dengan prefuran sebanyak 1-2 ppm selama 24 jam cukup efektif dalam mengendalikan penyakit ini (Tendencia and Lavilla-Pitogo, 2004).
4. Infeksi Yersinia ruckeri
4.1 Penyebab. Yersinia ruckeri dikenal juga sebagai penyakit enteric-red mouth (ERM) pada beberapa komoditas ikan laut. Secara klinis penyakit ini mudah dikenali karena terjadinya septikemia yang disertai dengan eksopthalmia, ascites, hemoragik serta borok. Secara umum, borok yang timbul terjadi pada rahang, langit-langit rongga mulut, insang dan operkulum
4.2 Pemicu infeksi. Infeksi Y. ruckerii sering dipicu oleh kondisi stress pada ikan yang
disebabkan oleh kualitas lingkungan yang buruk. Penyakit ERM ini juga dapat ditularkan secara langsung melalui kontak dengan ikan yang sakit atau carrier. Investigasi yang dilakukan oleh Hunter et al (1980) menunjukkan bahwa penyebaran Y. ruckeri dari ikan yang carier kepada ikan yang sehat terjadi ketika suhu meningkat menjadi 25⁰C. Bakteri ini dapat ditemukan pada ikan budidaya tanpa menunjukkan tanda-tanda penyakit. Dengan demikian organisme akuatik tersebut dapat berperan menjadi reservoir bagi munculnya wabah baru.
4.3 Dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan data distribusi penyakit, infeksi Y. ruckeri ini ditemukan pada komoditas Kerapu bebek dengan tingkat mortalitas rendah (<30%). Pada sejumlah kasus ERM, selain dari timbulnya hemoragik pada jaringan otot dan permukaan serosal intestinum, juga disertai dengan keluarnya cairan kuning pada saat perut ditekan di muara pengeluaran (Irianto, 2005). Bagaimana cara Y.ruckeri masuk kedalam tubuh inang belum dapat diketahui secara detail, namun usus dianggap sebagai lokasi utama berdasarkan pada isolat Y. ruckeri yang diperoleh dari saluran pencernaan setelah infeksi yang dilakukan pada skala laboratorium dan dari kejadian wabah alami (Busch & Lingg 1975; Valtonen et al. 1992).
4.4 Tindakan pengendalian. Untuk tahap pencegahan, hindari penanganan ikan yang kasar
untuk meminimalisasi terjadinya luka yang dapat menjadi portal bagi masuknya infeksi bakteri dikarenakan adanya kerusakan fisik. Selalu impor benih ikan yang telah memiliki Health certificate dan dari panti benih yang bersertifikat CPIB. Tahapan pencegahan lainnya dapat dilakukan dengan memperkuat sistem imun ikan melalui pemberian immunostimulan, vaksinasi dan pemberian probiotik serta meningkatkan kualitas air media pemeliharaan.
Tindakan pengendalian dapat dilakukan dengan melakukan karantina terhadap ikan yang terinfeksi dan memisahkannya dari ikan sehat. Di samping itu, aplikasi bahan herbal juga terbukti efektif untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh infeksi Y. ruckeri (Turker et al., 2009)
III.2.3 Penyakit Parasitik Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 7, 8, 9 dan 10 diketahui bahwa Trichodina sp, Benedenia sp, Diplectanum sp dan Cryptocaryon irritans menunjukkan insidensi dengan intensitas cukup tinggi pada budidaya ikan laut untuk komoditas ikan Kerapu (Epinephelus sp), Kakap putih (Lates calcarifer), Bawal Bintang (Trachinotus blochii) hingga ikan hias clown fish (Amphiprion sp). Sementara infestasi Haliotrema sp, Amyloodinium sp, Uronema sp, Rhexanella sp, Pseudorabdosynochus sp dan caligus sp memiliki tingkat intensitas yang moderat. 1. Infeksi Parasit Protozoa 1.1 Penyebab. Berdasarkan data diketahui bahwa infeksi parasit protozoa disebabkan oleh
Trichodina sp dari kelompok ciliata, Cryptocaryon irritans dan Amyloodinium sp dari kelompok dinoflagellata
1.2 Pemicu infeksi. Infestasi Trichodina sp, Cryptocaryon irritans dan Amyloodinium sp
umumnya dipicu oleh kondisi kualitas air dan pertukaran air yang buruk, kondisi inang yang lemah dan padat tebar yang tinggi (Colorni, 1987). Lebih spesifik, Cryptocaryon irritans akan berkembang dengan baik dan mulai menginfeksi ikan bila suhu meningkat pada kisaran 27-30⁰ C (Dan et al., 2009; Dickerson, 2006). Sementara, infeksi Amyloodinium sp selain dipicu oleh peningkatan suhu juga dipicu oleh kondisi salinitas yang optimal, yaiut berada pada kisaran 16 – 29 ppt (Reed and Francis-floyd, 1994).
1.3 Dampak yang ditimbulkan. Trichodina spp dapat menyebabkan kematian yang tinggi pada ikan budidaya dimulai dari fase benih hingga tahapan induk. Kemampuan Trichodina untuk memperbanyak diri dengan cepat pada kondisi lingkungan tertentu atau ketika ikan mengalami stress akibat berbagai faktor lingkungan menyebabkan mortalitas pada ikan budidaya semakin meningkat (Smith and Noga, 1992). Data pemantauan menunjukkan bahwa infestasi Parasit Cryptocaryon irritans dapat menyebabkan mortalitas hingga > 60% utamanya pada ikan Kerapu dan clown fish. Sementara infestasi Amyloodinium sp berdampak pada tingkat kelulushidupan ikan budidaya pada fase benih dan induk dengan tingkat mortalitas mencapai 60%
1.4 Tindakan pengendalian. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari
infestasi parasit ini adalah dengan menerapkan pola pendekatan prophylaksis melalui pemberian immunostimulan dan vitamin untuk memperkuat sistem imun, menerapkan sistem biosecurity dan selalu memperhitungkan posisi jaring pada unit perbesaran agar tidak terlalu dangkal pada saat surut untuk menghindari transmisi parasit. Disamping itu, kebersihan bak dan pengelolaan kualitas air yang baik dengan sistem filtrasi mekanik, biologi serta kimiawi yang dilengkapi dengan perlakuan UV ultraviolet dan ozon dapat mengurangi kemungkinan keberadaan parasit didalam media pemeliharaan.
Trichodina sp dapat dikendalikan dengan perendaman air tawar selama 1 jam untuk 3 hari secara berurutan, perendaman dengan formalin 200 ppm selama 30-60 menit dengan aerasi kuat atau perendaman formalin dengan konsentrasi 25 ppm selama 1-2 hari (Cruz-Lacierda and Erazo Pagador, 2004).
Cryptocaryon irritans dapat dikendalikan dengan perendaman menggunakan copper sulphate (CuSO4) dengan konsentrasi 0,5 ppm selama 5-7 hari dengan aerasi kuat dan air yang digunakan selama masa pengobatan harus diganti setiap hari. Ikan yang terinfeksi sebaiknya dipindahkan ke bak yang bebas parasit Cryptocaryon irritans sebanyak 2-3 kali dengan interval 3 hari.
Tindakan pengendalian infeksi Amyloodinium sp dapat dilakukan dengan perendaman
menggunakan bahan kimia copper sulphate (CuSO4) dengan konsentrasi 0,5 ppm selama 3-5 hari atau direndam menggunakan formalin dengan konsentrasi 200 ppm selama 30-60 menit dengan aerasi kuat. Ikan yang diobati harus dipindahkan ke bak yang bebas parasit dan bersih dua kali dengan interval 3 hari.
2. Infeksi Parasit Non-Protozoa 2.1 Penyebab. Berdasarkan data diketahui bahwa infeksi parasit non- protozoa disebabkan
oleh Benedenia, Neobenedenia, Diplectanum dan Haliotrema untuk kelompok Trematoda monogenea, Caligus spp dan Rhexanella sp untuk golongan crustacean dan Microcotylid monogenea, Uronema sp, Pseudorabdosynochus sp dan Hirudinea sp dari kelompok annelida
2.2 Pemicu infeksi. Parasit non-protozoa umumnya dipicu oleh kualitas air yang buruk, kondisi stress pada ikan baik oleh lingkungan ataupun penanganan ikan yang kurang baik, kualitas pakan (pellet ataupun rucah) yang buruk, padat tebar tinggi, kurangnya pergantian air dan kondisi lingkungan yang optimal bagi proses perkembangan parasit.
2.3 Dampak yang ditimbulkan. Infestasi parasit Benedenia sp sering mengakibatkan
kematian pada ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) dengan tingkat mortalitas 40 – 50% akibat keterlambatan dan ketidaksesuaian tindakan pengendalian yang dilakukan oleh pembudidaya. Kematian tinggi akibat infestasi parasit Diplectanum sp. dapat mencapai hingga 50% bila parameter kualitas air yang berkaitan dengan konsentrasi ammonia mengalami peningkatan yang nyata (Novriadi, 2014)
2.4 Tindakan pengendalian. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari
infestasi parasit ini adalah dengan menerapkan pendekatan prophylaksis melalui pemberian immunostimulan dan vitamin untuk memperkuat sistem imun, menerapkan sistem biosecurity dan selalu memperhitungkan posisi jaring pada unit perbesaran agar tidak terlalu dangkal pada saat surut untuk menghindari transmisi parasit. Disamping itu, kebersihan bak dan pengelolaan kualitas air yang baik dengan sistem filtrasi mekanik, biologi serta kimiawi yang dilengkapi dengan perlakuan UV ultraviolet dan ozon dapat mengurangi kemungkinan keberadaan parasit didalam media pemeliharaan.
Tindakan pengendalian infeksi cacing dapat dilakukan dengan menggunakan antihelmintik,
akan tetapi harus didahului dengan suatu diagnose yang baik dan benar.pengobatan nematode hanya dapat dilakukan dengan fenbendazole an levamisole. Penggunaan levamisole dapat dilakukan dengan mencampurnya dengan pakan (sekitar 3,5 gr per kg pakan) dan diberikan sekali seminggu slama tga minggu.
Pengendalian masalah infestasi monogenea biasanya tidak akan memuaskan tanpa usaha
menghilangkan penyebab utamanya. Pengobatan menggunakan formalin dapat dilakukan dengan disertai aerasi kuat. Selama pengobatan dengan menggunakan formalin ini harus selalu diawasi. Jika terjadi reaksi yang tidak diinginkan, ikan harus segera diambil dan ditempatkan pada bak yang bersih.
IV. Kesimpulan
1. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa infeksi nodavirus sebagai agen penyebab Viral Nervous Necrosis dan iridovirus sebagai agen penyakit viral pada budidaya ikan laut di Indonesia
2. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa keberadaan bakteri Vibrio alginolyticus, V. parahaemolyticus, V. fluvialis, V. vulnificus, V. damsela, V. anguillarum, V. harveyi, V. charchariae, Pseudomonas, Flexibacter sp, dan Yersinia ruckeri menjadi penyebab utama penyakit infeksi bakterial pada budidaya ikan laut di Indonesia
3. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa parasit Trichodina sp, Benedenia sp, Diplectanum sp dan Cryptocaryon irritans menunjukkan insidensi dengan intensitas cukup tinggi pada budidaya ikan laut untuk komoditas ikan Kerapu (Epinephelus sp), Kakap putih (Lates calcarifer), Bawal Bintang (Trachinotus blochii) hingga ikan hias clown fish (Amphiprion sp). Sementara infestasi Haliotrema sp, Amyloodinium sp, Uronema sp, Rhexanella sp, Pseudorabdosynochus sp dan caligus sp memiliki tingkat intensitas moderat pada budidaya ikan laut di Indonesia
4. Pendekatan prophylaksis seperti aplikasi Vaksinasi, Immunostimulan, Probiotik dan perbaikan kualitas air menjadi strategi alternatif untuk menggantikan antibiotika dan penggunaan bahan kimia dalam tindakan pengendalian penyakit ikan
V. Daftar Pustaka Aldeman, D.J. dan Hastings, T.S. (1998). Antibiotic use in aquaculture: development of antibiotic
resistance-potential for consumer health risks. Int. J. Food Sci. Technology (33): 139-155. Austin, B dan Austin D.A. (1999). Bacterial fish pathogens, Diseases of farm and wild fish. 3rd
(revised) edition. Springer-Praxis, Goldaming. Bondad-Reantaso, M.G., Subasinghe, R.P., Arthur, J.R., Ogawa, K., Chinabut, S., Adlard, R, Tan,
Z. & Shariff, M. (2005). Disease and health management in Asian aquaculture. Vet. Parasitol. 132:249-272.
Busch R.A. & Lingg A.J. (1975) Establishment of an asymptotic carrier state infection of enteric redmouth disease in rainbow trout (Salmo gairdneri). Journal of the Fisheries Research Board of Canada (32): 2429-2432.
Cabello, F.C. 2006. Heavy use of prophylactic antibiotics in aquaculture: a growing problem for human and animal health and for the environment. Environ Microbiol (8): 1137-1144.
Cao, L., W. Wang, Y. Yang, C. Yang, Z. Yuan, S. Xiong and J. Diana. (2007). Environmental impact of aquaculture and countermeasures to aquaculture pollution in China. Environmental Science in Pollution Res 14 (7): 452 – 46
Chong, Y.C. and T.M. Chao. (1986). Common Diseases of Marine Foodfish. Fisheries Handbook No. 2. Primary Production Departement. Ministry of National Development. Republic of Singapore. 33p.
Colorni, A. (1987). Biology of Cryptocaryon irritans and strategies for its control. Aquaculture (67): 236-237
Dan, X.M., X.T. Lin, Y.X Yan, N. Teng, Z.L. Tan, and A.X. Li. (2009). A technique for the preservation of Cryptocaryon irritans at low temperatures. Aquaculture (297): 112–115.
Danayadol, Y., Direkbusarakom, S., Boonyaratpalin, S., Miyazaki, T. and Miyata, M. (1997). Iridovirus infection in brown-spotted grouper (Epinephelus malabaricus) cultured in Thailand. In: Flegel, T.W and MacRae, I.H. (eds) Diseases in Aquaculture III. Fish Health Section. Asian Fisheries Society. Manila. Pp.67-72
Defoirdt, T., Bossier, P., Sorgeloos, P. and Verstraete, W. (2005). The impact of mutations in the quorum sensing systems of Aeromonas hydrophila, Vibrio anguillarum and Vibrio harveyi on their virulence towards gnotobiotically cultured Artemia franciscana. Environmental Microbiology 7 (8): 1239–1247.
Dickerson, H.W. (2006). Ichthyophthirius multifiliis and Cryptocaryon irritans (Phylum Ciliophora). Pages 116–153 In Woo, P.T.K., ed. Fish diseases and disorders vol.1: protozoan and metazoan disorders. 2nd ed. CAB International. Cambridge, MA.
Fris Johnny dan Des Roza, (2009). Kasus infeksi irido pada benih ikan kerapu pasir, Epinephelus corralicola di hatchery. Jurnal Perikanan (J. Fish . Sci.) XI (1): 8-12
Gibson-Kueh, S. (2012). Diaseases of Asian Seabass (or Barramundi), Lates calcarifer Bloch. Ph.D Thesis. Murdoch University. Australia.
Hill, B.J. (2005) The need for effective disease control in international aquaculture. Dev. Biol. (Basel) (121): 3–12.
Irianto, A. (2005). Patologi Ikan Teleostei. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
Kasornchandra, J. and Klongpradit, R. (1997). Iolation and preliminary characterization of a pathogenic iridovirus in nursing grouper, Epinephelus malabaricus. In: Flegel, T.W and MacRae, I.H. (eds) Diseases in Aquaculture III. Fish Health Section. Asian Fisheries Society. Manila.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2009). Kelautan dan Perikanan dalam Angka. Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP. Jakarta.
Kusuda, R., Kawai, T., Toyoshima, T. dan Komatsu, I. (1976). A new pathogenic bacterium belonging to the genus Streptococcus isolated from an epizootic of cultured yellowtail. Bull. Jpn. Soc. Sci. Fish 42: 1345-1352
Koesharyani, I., D. Roza., K. Mahardika, F. Jhonny, Zafran, dan K. Yuasa. (2001). Penuntun Diagnosa Penyakit Ikan II. Penyakit Ikan Laut dan Krustacea di Indonesia. Balai Penelitian Perikanan Laut Gondol-Singaraja. 49 pp.
Krovacek, K., Faris, A., Ahne, W., and Mansson, I. (1987) Adhesion of Aeromonas hydrophila and Vibrio anguillarum to fish cells and to mucus-coated glass slides.FEMS Microbiol Lett (42): 85-89.
Kusumastanto, T. (2003). Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan dan Perhubungan Laut dalam Abad XXI. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor.
Leong, T.S (1994). Parasites and diseases of cultured marine finfish in southeast asia. Universiti Sains Malaysia, 25 pp
Leong, T.S and Colorni, A. (2002). Infectious diseases of warmwater fish in marine and brackish waters. In: Woo, P.T.K., Bruno, D.W., Lim, L.H.S. Diseases and disorders of finfish in cage culture. CABI publishing. United Kingdom.
MacDiarmid, S.C. 1997. Risk analysis, international trade, and animal health. In Fundamentals of risk analysis and risk management (V. Molak, ed.). CRC Lewis Publishers, Boca Raton, 377-387.
Mahardika, K., Zafran, D. Roza, F. Johnny, A. Prijono. (2002). Studi pendahuluan penggunaan vaksin iridovirus (inaktif vaksin) pada juvenile kerapu lumpur, Epinephelus coioides. Laporan Hasil Penelitian DIP 2002 Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut Gondol, Gondol.
Mangunwiryo, H. (1990). Pengenalan Penyakit Virus pada Ikan dan Udang serta Kemungkinan Pengendaliannya. Seminar Nasional II Penyakit Ikan dan Udang Tanggal 16 – 18 Januari 1990. Balai Penelitian Perikanan Air Tawar Bogor. Hal. 1 – 9.
Nakajima, K., Maeno, Y., Fukudome, M., Fukuda, Y., Tanaka, S., Matsuoka, S. and Sorimachi, M. (1995). Immunofluorescence test for the rapid diagnosis of red seabream iridovirus infection using monoclonal antibody. Fish pathology (30): 115-119.
Nakajima, K., Maeno, Y., Kurita, J. and Inui, Y. (1997). Vaccination against red seabream iridoviral disease in red seabream. Fish pathology (18): 99-101
Pedersen, K., and Larsen, J.L. (1998) Characterization and typing methods for the fish pathogen Vibrio anguillarum. In Recent Research Developments in Microbiology. 2: 17-93.
Plumb, J.A., Schachte, J.H., Gaines, J.L., Peltier, W., dan Carrol, B. (1974). Streptococcus sp from marine fish along the Alabama and northwest florida coast of the Gluf of Mexico. Trans. Am. Fish. Soc 103: 358 – 361.
Post, G. (1987). Texbook of Fish Health. T.F.H. Publications Inc. USA. 288 pp. Putri, R.R., Yanuhar, U. dan Suryanto, A.M.H. (2013). Perubahan struktur jaringan mata dan
otak pada larva ikan kerapu tikus (Cromileptes altivelis) yang terinfeksi Viral Nervous Necrosis (VNN) dengan pemeriksaan Scanning Electron Microscope (SEM). MSPi Student Journal (1) : 1-10
Schubert, G. (1987). Fish Diseases a Complete Introduction. T.F.H. Publications Inc. USA. 125 pp. Smith, S.A. and E.J. Noga. (1992). General Parasitology. In Fish Medicine. M.K. Stoskopf, ed.
W.B. Saunders Co. Philadelphia, PA. Subasinghe, R. dkk. (2001). Aquaculture development, health and wealth. In aquaculture in the
third millennium. Technical proceedings of the conference on aquaculture in the third millennium (Subasinghe, R.P. et al., eds). pp. 167-191. Bangkok and FAO, NACA
Subasinghe, R. (2009). Disease control in aquaculture and the responsible use of veterinary drugs and vaccines : the issues, prospects and challenges. In : Rogers C. (ed.), Basurco B. (ed.). The use of veterinary drugs and vaccines in Mediterranean aquaculture. Zaragoza : CIHEAM, 2 009 . p. 5-11 (Option s Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerran éens; n . 86)
Sukadi, F. (2004). Kebijakan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan dalam Mendukung Akselerasi Pengembangan Perikanan Budidaya. Dalam: Prosiding Pengendalian Penyakit pada Ikan dan Udang Berbasis Imunisasi dan Biosecurity, Unsoed Purwokerto. Hal 1 – 7.
Toranzo, A.E., Magarinos, B., Romalde, J.L. (2005). A review of the main bacterial fish diseases in mariculture systems. Aquaculture 246: 37– 61
Trobos. (2011). Vaksin ikan: digadang tapi belum dipercaya. Akses: http://www.trobos.com/2014/detail_berita.php?sid=2833&sir=12, Tanggal 12 Juli 2014.
Turker, H., Yıldırım, A. B. and Karakaş, F. P. (2009). Sensitivity of Bacteria Isolated from Fish to Some Medicinal Plants. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (9): 181- 186 DOI: 10.4194/trjfas.2009.0209.
Valtonen E.T., Rintamäki P. & Koskivaara M. (1992) Occurence and pathogenicity of Yersinia ruckeri at fish farms in northern and central Finland: do wild fish serve as a source of infection? Journal of Fish Diseases (15): 163-171.
Warintek. (2001). Pedoman teknis penanggulangan penyakit ikan budidaya laut. Kantor Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jakarta.
Woo, P.T.K., Bruno, D.W., Lim, L.H.S. (2002). Diseases and disorders of finfish in cage culture. CABI publishing. United Kingdom. pp. 203
Yuasa, K.,D. Roza, I.Koesharyani, F. Johnny, and K. Mahardika. (2000). General Remarks on Fish Disease Diagnosis. Pp. 5-18. Textbook for the Training Course on Fish Disease Diagnosis. Lolitkanta-JICA Booklet No.12.
Yuasa, K., I. Koesharyani, D. Roza, F. Jhonny, and Zafran. (2001). Manual for PCR Procedure; Rapid diagnosis on Viral Nervous Necrosis (VNN) in Grouper. Lolitkanta-JICA Booklet No. 13, 35 pp
Zafran, I. Koesharyani dan K. Yuasa. (1997). Parasit Pada Ikan Kerapu di Panti Benih dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia. Vol. III(4):16-23.