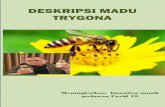BAB II madu jadi
Transcript of BAB II madu jadi
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Kulit
2.1.1 Anatomi dan Fisiologi Kulit
Kulit merupakan organ kompleks yang melindungi
dari lingkungan, pada saat bersamaan memungkinkan
interaksi dengan lingkungannya. Kulit merupakan
perpaduan yang dinamis, kompleks, terintegrasi
dari sel, jaringan, dan elemen matriks yang
memediasi berbagai fungsi, yaitu: kulit merupakan
barier permeabilitas fisik, menjaga dari agen
infeksius, termoregulasi, proteksi sinar
ultraviolet, penutupan luka dan regenerasi, dan
memberikan penampilan fisik luar (Kochevar dkk,
2008). Kulit terdiri dari tiga lapisan besar,
yaitu epidermis, dermis, dan subkutis.
2.1.2 Epidermis
Epidermis merupakan struktur yang terus
memperbaharui diri secara kontinyu, yang
memberikan tempat tumbuh bagi struktur turunan
9
10
yang disebut appendage (kelompok pilosebaseus,
kuku, dan kelenjar keringat). Ketebalan epidermis
berkisar antara 0,4 sampai 1,5 mm dibandingkan
dengan kedalaman kulit 1,5 sampai 4,0 mm. Sebagian
besar epidermis terdiri dari sel keratinosit
yangmengelompok menjadi empat lapisan, yang diberi
nama sesuai dengan posisi atau sel pembentuk
strukturnya. Sel tersebut berdiferensiasi
progresif dari sel basal proliveratif, melekat
dengan epidermal membran basal, menuju
diferensiasi akhir stratum korneum
terkeratinisasi, yang merupakan lapisan terluar
dan barier kulit.
Epidermis terdiri dari 5 lapis, yaitu stratum
germinativum (SG), stratum spinosum (SS), stratum
granulosum (SGR), stratum lusidum dan stratum korneu (SC)
dimana keratinosit bermigrasi ke permukaan dan
kemudian terlepas, yang disebut dengan proses
deskuamasi. (Melton dan Swanson, 1996). Lapisan
epidermis terdiri dari :
11
2.1.2.1 Lapisan basal/stratum germinativum, lapisan ini
aktif bermitosis , terdiri dari sel keratinosit
berbentuk kolumnar yang melekat melalui filamen
keratin pada membran basal pada hemidesmosom,
melekat pada sel sekitar lainnya sepanjang
desmosom, dan memberikan pertumbuhan bagi sel yang
lebih superfisial untuk membentuk lapisan
epidermis. Analisis ultrastruktur menunjukkan
adanya membran yang berikatan dengan vakuola yang
mengandung melanosom berpigmen yang ditransfer
dari melanosit melalui fagositosis. Pigmen
sepanjang melanosom memberikan keseluruhan
pigmentasi kulit secara makroskopis. Lapisan basal
merupakan lokasi primer dari sel epidermis yang
aktif membelah.
2.1.2.2 Lapisan spinosum, bentuk, struktur, bagian
subseluler dari sel spinosus berhubungan dengan
posisinya pada pertengahan epidermis. Lapisan ini
diberi nama karena penampakannya yang menyerupai
spine (duri) pada bagian tepinya dilihat secara
histologis. Sel spinosus suprabasal berbentuk polihedral
12
dengan inti bulat. Sel ini berdiferensiasi dan
bergerak ke atas sepanjang epidermis, dan secara
progresif memipih dan berkembang menjadi organel
yang dikenal sebagai granula lamelar.
2.1.2.3 Lapisan granular, lapisan ini diberi nama
sesuai dengan granula keratohialin basofilik yang
prominen disekitar sel. Lapisan granuler adalah
tempat pembentukan komponen struktural yang akan
membentuk barier epidermal. Granula keratohialin
terbentuk utamanya dari profilagrin, filament
keratin, dan lorikrin. Profilagrin akan berubah
menjadi filagrin, dimana filagrin berperan pada
hidrasi stratum korneum dan membantu filter
radiasi ultraviolet.
2.1.2.4 Stratum korneum, lapisan ini terbentuk dari
difrensiasi komplit sel granular yang menghasilkan
tumpukan sel tak berinti dan berbentuk kerucut
memipih. Lapisan ini memberikan proteksi mekanik
kulit dan barier kehilangan air dan permeabilitas
terhadap substrat yang larut dari lingkungan.
Barier stratumkorneum terbentuk dari dua sistem
13
kompartemen dengan lemak tipis, korneosit yang
kaya protein dikelilingi oleh matriks lemak
ekstraseluler. Kedua kompartemen bekerja bersama-
sama membentuk barier aktivitas epidermis. Fungsi
primer dari dari matriks lemak ekstraseluler
adalah regulasi permeabilitas, deskuamasi,
aktivitas peptida antimikrobial, eksklusi toksin,
dan absorpsi kimia selektif. Korneosit berperan
pada penjagaan mekanik, hidrasi, inflamasi yang
dimediasi oleh sitokin, dan proteksi dari
kerusakan akibat sinar matahari.
2.1.3 Dermis
Dermis merupakan sistem integrasi dari fibrus,
filamentus, difus, dan elemen seluler jaringan
penghubung yang mengakomodasi saraf, jaringan
pembuluh darah, appendage epidermal, dan terdiri
dari berbagai tipe sel, termasuk fibroblas,
makofag, sel mast, dan sel yang berperan pada
sistem imun. Dermis merupakan komponen terbesar
pembentuk kulit sehingga mempertahankan
viabilitas, elastisitas dan kekuatan peregangan
14
kulit. Ini melindungi tubuh dari trauma mekanik,
mengikat air, dan berperan pada termoregulasi, dan
mengandung reseptor berbagai stimulus. Dermis
bekerjasama dengan epidermis dalam mempertahankan
komponen masing-masing serta berinteraksi dalam
perbaikan dan pembentukan kembali kulit setelah
perlukaan. Dermis terdiri dari dua bagian, yaitu :
papiler dermis dan retikuler dermis. Kedua bagian tersebut
dapat dibedakan secara histologis, dan keduanya
berbeda dalam hal organisasi jaringan penunjang,
densitas sel, bentuk saraf dan pembuluh darah.
Papiler dermis berbatasan dengan epidermis, dengan
ketebalan tidak lebih dari dua kalinya. Retikuler
dermis benjolan jaringan dermal. Ini terbentuk
sebagian besar dari serat kolagen berdiameter
besar, menyatu membentuk rangkaian, cabang serat
elastin mengelilingi rangkaian tersebut. Pada
orang normal, serat elastin dan rangkaian kolagen
meningkat ukurannya secara progresif sampai ke
hipodermis. Bagian terbawah dari retikuler dermis
dikatakan transisi dari jaringan penunjang fibrus
dengan jaringan penunjang lemak dari hipodermis.
15
2.1.4 Hipodermis (subkutis)
Jaringan hipodermis menyekat tubuh, sebagai bantalan
dan pelindung kulit, dan memungkinkan mobilitas
kulit dari jaringan di bawahnya. Jaringan ini juga
memberikan efek kosmetik dengan memberikan bentuk
tubuh. Lapisan retikuler dermis (RD) terdiri dari
jaringan ikat yang rapat, yang dibedakan dari
lapisan papiler dermis (PD), terutamanya dibentuk
dari jaringan ikat longgar. Elastisitas dan
regangan kulit terutama ditentukan oleh lapisan
RD, yang juga merupakan tempat struktur lain
seperti kelenjar dan folikel rambut (Melton dan
Swanson, 1996).
2.2 Konsep Luka
2.2.1 Definisi
Luka adalah rusaknya struktur dan fungsi anatomi
normal yang diakibatkan oleh proses patologis yang
berasal dari faktor internal dan eksternal yang
mengenai organ tertentu (Perry, 2006: 1853).
16
Luka adalah kerusakan kontinuitas jaringan atau
kulit, mukosa mambran dan tulang atau organ tubuh
lain (Mansjoer, 2000: 396).
2.2.2 Jenis-jenis luka
2.2.2.1 Berdasarkan sifat kejadian.
1) Luka disengaja, misalnya luka terkena radiasi
atau bedah
2) Luka tidak disengaja, dibagi menjadi dua yaitu
luka terbuka (jika terjadi robekan) dan luka
tertutup (jika tidak terjadi robekan).
2.2.2.2 Berdasarkan penyebabnya, luka dibagi menjadi
dua, yaitu luka mekanisme dan non-mekanisme
1) Luka mekanik terdiri atas :
(1) Vulnus Scissum atau luka sayat akibat
benda tajam. Pinggir luka kelihatan rapi.
(2) Vulnus Contusum, luka memar karena
cedera pada jaringan bawah yang menyebabkan
robeknya jaringan rusak dalam.
(3) Vulnus Kaceratum, luka robek akibat
terkena mesin atau benda lainnya yang
menyebabkan robeknya jaringan rusak dalam.
17
(4) Vulnus Punctum, luka tusuk yang kecil di
bagian luar (bagian mulut luka) akan tetapi
besar didalam luka.
(5) Vulnus Seloferadum, luka tembakan
peluru.
(6) Vulnus Morcun, luka gigitan yang tidak
jelas bentuknya pada bagian luka.
(7) Vulnus Abrasio, luka terkikis yang
terjadi pada bagian luka dan tidak sampai ke
pembuluh darah
2) Luka non-mekanik terdiri atas luka akibat zat
kimia, termik, radiasi, atau sengatan listrik.
2.2.3 Tahapan Penyembuhan Luka
Tanpa memandang penyebab, tahapan penyembuhan luka
terbagi atas :
2.2.3.1 Fase koagulasi: setelah luka terjadi, terjadi
perdarahan pada daerah luka yang diikuti dengan
aktifasi kaskade pembekuan darah sehingga
terbentuk klot hematoma. Proses ini diikuti oleh
proses selanjutnya yaitu fase inflamasi.
18
2.2.3.2 Fase inflamasi: Fase inflamasi mempunyai
prioritas fungsional yaitu menggalakkan
hemostasis, menyingkirkan jaringan mati, dan
mencegah infeksi oleh bakteri patogen terutama
bakteria. Pada fase ini platelet yang membentuk
klot hematom mengalami degranulasi, melepaskan
faktor pertumbuhan seperti platelet derived growth
factor (PDGF) dan transforming growth factor ß (βTGF),
granulocyte colony stimulating factor (G-CSF), C5a,
TNFα, IL-1 dan IL-8. Leukosit bermigrasi menuju
daerah luka.Terjadi deposit matriks fibrin yang
mengawali proses penutupan luka.
2.2.3.3 Fase proliperatif: Fase proliperatif terjadi
dari hari ke 4-21 setelah trauma. Keratinosit
disekitar luka mengalami perubahan fenotif.
Regresi hubungan desmosomal antara keratinosit
pada membran basal menyebabkan sel keratin
bermigrasi kearah lateral. Keratinosit bergerak
melalui interaksi dengan matriks protein
ekstraselular (fibronectin, vitronectin dan
kolagen tipe I). Faktor proangiogenik dilepaskan
19
oleh makrofag, vascular endothelial growth factor (VEGF)
sehingga terjadi neovaskularisasi dan pembentukan
jaringan granulasi.
2.2.3.4 Fase remodeling: Remodeling merupakan fase
yang paling lama pada proses penyembuhan luka,
terjadi pada hari ke 21-hingga 1 tahun. Terjadi
kontraksi luka, akibat pembentukan aktin
myofibroblas dengan aktin mikrofilamen yang
memberikan kekuatan kontraksi pada penyembuhan
luka. Pada fase ini terjadi juga remodeling
kolagen. Kolagen tipe III digantikan kolagen tipe
I yang dimediasi matriks metalloproteinase yang
disekresi makrofag, fibroblas, dan sel endotel.
Pada masa 3 minggu penyembuhan, luka telah
mendapatkan kembali 20% kekuatan jaringan normal.
Tabel 2.1 Penyembuhan Luka Bedah Menurut Barbara
(2005).
Stadium Waktu Kejadian SelPeradangan(0-4hari)
0-2 jam
0-4 hari
1. Hemostasis2. Fagositosis
1. Trombosit2. Eritrosit3. Leukosit4. Neutrofil5. Makrofag
20
Poliferasi(2-22hari)
1-4 hari1-7 har
i2-20hari2-22hari
1. Epitelisasi
2. Neovaskularisasi
3. Kontraksi4. Sintesiskolagen
1. Keratinosit
2. Entotel3. Miofibrobl
as4. Fibroblas
Pematangan(21hari-2 tahun)
Remodelingkolagen
Fibroblas
Tabel 2.2 Tanda-Tanda Penyembuhan Luka BedahMenurut Barbara (2005)
Stadium Waktu Tanda-TandaPeradangan(0-4 hari)
0-2 jam0-4 hari
Terasa panas,nyeri, kemerahan,terjadipembengkakan.
Proliferasi(2-22 hari)
1-4 hari2-7 hari2-20 hari2-22 hari
Tepi luka tampakmerah muda,tampak cerah,ridge, tampakjaringan epiteldan granulasi.
Pematangan(21hari-2tahun)
Jaringan parut,tampak seratberbentuk silang,area luka terasagatal.
2.2.4 Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Penyembuhan
Luka
21
2.2.4.1 Vaskularisasi, karena luka membutuhkan
keadaaan peredaran darah yang baik untuk
pertumbuhan atau perbaikan sel.
2.2.4.2 Anemia, memperlambat proses penyembuhan luka
mengingat perbaikan sel membutuhkan kadar protein
sel yang cukup. Oleh sebab itu, orang yang
mengalami kekurangan kadar hemoglobin dalam darah
akan mengalami proses penyembuhan lama.
2.2.4.3 Usia, kecepatan perbaikan sel berlangsung
sejalan dengan pertumbuhan atau kematangan usia
seseorang. Namun selanjutnya, proses penuaan dapat
menurunkan sistem perbaikan sel sehingga dapat
memperlambat proses penyembuhan luka.
2.2.4.4 Penyakit lain, mempengaruhi proses
penyembuhan luka. Adanya penyakit seperti diabetes
millites dan ginjal dapat memperlambat proses
penyembuhan luka.
2.2.4.5 Nutrisi, merupakan unsur utama dalam membantu
perbaikan sel, terutama karena kandungan zat gizi
yang terdapat di dalamnya. Sebagai contoh vitamin
A diperlukan untuk membantu proses epitelisasi
22
atau penutupan luka dan sintesis kolagen, vitamin
B kompleks sebagai faktor pada sistem enzim yang
mengatur metabolisme protein , karbohidrat lemak,
vitamin C dapat berfungsi sebagai fibroblas dan
pencegah adanya infeksi serta membentuk kapiler
darah dan vitamin K membantu sintesis protrombin
dan berfungsi sebagai zat pembekuan darah.
2.2.4.6 Kegemukan, obat-obatan, merokok dan stres.
Mempengaruhi proses penyembuhan luka.
2.2.4.7 Infeksi, terjadi bila terdapat tanda-tanda
seperti kulit kemerahan, demam, nyeri dan timbul
bengkak, jaringan disekitar luka mengeras,serta
adanya kenaikan leukosit (Musrifatul Uliyah,
2006).
2.3 Tikus putih (Rattus norvegicus)
Tikus putih (Rattus norvegicus) merupakan salah satu
hewan percobaan yang paling sering digunakan dalam
penelitian penelitian oleh karena memiliki
strukturanatomi, fisiologi dan histologi organ yang
secara sistematis hampir sama dengan organ manusia.
23
Selain itu, tikus putih lebih mudah didapatkan,
lebih mudah dipelihara, lebih cepat berkembang
menjadi dewasa, tidak memperlihatkan perkawinan
musiman dan umumnya lebih mudah berkembang biak.
Tikus termasuk hewan mamalia, oleh sebab itu
dampaknya terhadap suatu perlakuan mungkin tidak
jauh berbeda dibanding dengan mamalia lainnya
(Gunter dan Dhand, 2002). Klasifikasi tikus putih
adalah sebagai berikut:
Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Mamalia
Ordo : Rodentia
Famili : Muridae
Genus : Rattus
Spesies : Rattus norvegicus
Tikus dan manusia mempunyai jumlah gen pengkode
protein yang sama, yaitu sekitar 30.000, dengan
tingkat kemiripan sebesar 99%. Dalam sebuah
penelitian oleh Dermitzakis yang langsung
24
membandingkan urutan kromosom 21 pada manusia dengan
kromosom pada tikus, didapatkan bahwa bahkan daerah
kromosom yang miskin gen menunjukkan kesamaan yang
luas antara dua organisme ini (Gunter dan Dhand,
2002).
2.3.1 Kandang
Kandang hewan sebaiknya terbuat dari bahan yang
kuat dan awet. Untuk mempermudah pembersihan dan
sanitasi kandang sebaiknya permukaan kandang harus
rata. Dirancang sedemikian rupa agar pengamatan
terhadap hewan yang ada di dalam kandang tidak
terlalu mengganggu ketenangan hewan tersebut.
Ukuran kandang tikus yang digunakan adalah 1800cm²
untuk 7-8 ekor.
Posisi tempat makanan dan minuman dibuat agar
pencucian, penggantian dan pengisian kembali mudah
dilakukan. Kandang yang rusak harus segera
diperbaiki untuk mencegah hewan terluka.
2.3.2 Alas Kandang
25
Alas kandang harus bersifat menyerap air bebas
dari bahan kimia yang bersifat toksin atau zat
lain yang berbahaya bagi hewan dan pekerja dan
merupakan pekerja dan merupakan bahan yang tidak
bisa dimakan hewan. Jumlah yang dipakai harus
cukup untuk menjaga hewan tetap kering sampai
jadwal pergantian berikutnya (Harmita, 2005).
2.3.3 Makanan dan Minuman
Makan tikus yang sama yaitu biji jagung muda,
setiap hari 12-20 gr makanan. Tikus tidak
memerlukan minuman karena sudah mendapatkan air
dari makanan yang dimakannya.
Jika makanan tidak mengandung air maka sebaiknya,
air minum intuk hewan harus selalu tersedia.
Dengan perlakuan tertentu, kontaminasi di dalam
air bisa dikurangi (Harmita, 2005).
2.3.4 Penyembuhan Luka Pada Tikus Putih
Tikus putih dan manusia mempunyai tingkat homologi
yang tinggi. Sehingga dalam proses perbaikan
luka,tikus putih memiliki fase-fase perbaikan luka
26
yang sama dengan manusia, dengan aktivitas
mediator yang juga sama (Sheid dkk, 2000). Fase
pertama yaitu fase inflamasi, dimana terjadi
reaksi vaskuler dan seluler akibat luka yang
terjadi pada jaringan lunak. Pada fase ini terjadi
penghentian perdarahan serta pembersihan daerah
luka dari benda asing, sel-sel mati serta bakteri
sebagai persiapan mulainya penyembuhan luka. Pada
awal fase, kerusakan pembuluh darah menyebabkan
keluarnya platelet yang berfungsi sebagai
hemostasis. Platelet akan membentuk clot yang akan
menutupi pembuluh darah yang rusak selain itu juga
dilepaskan zat vasokonstriktor yang akan akibatkan
vasokonstriksi pembuluh darah kapiler, dan akan
terjadi penempelan endotel pada pembuluh darah
(Hoyt dkk, 2007). Fase ini tidak berlangsung lama,
setelah itu akan terjadi vasodilatasi kapiler
serta pelepasan vasodilator seperti histamin,
serotonin dan sitokin. Histamin akan menyebabkan
vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vena,
sehingga cairan plasma darah keluar dari pembuluh
27
darah dan masuk ke daerah luka. Terjadi edema
jaringan dan keadaan lokal lingkungan luka menjadi
asidosis. Eksudasi ini juga mengakibatkan migrasi
sel lekosit (terutama netrofil) ke ekstra
vaskuler. Fungsi netrofil adalah fagositosis benda
asing dan bakteri di daerah luka selama dua sampai
tiga hari dan kemudian akan digantikan oleh sel
makrofag yang berperan lebih besar jika dibanding
dengan netrofil pada proses penyembuhan luka. Fase
inflamasi dapat berlangsung sampai hari ketiga
(Hoyt dkk, 2007). Fase berikutnya yaitu fase
proliferasi. Peran fibroblas sangat besar pada
fase ini, yaitu bertanggung jawab pada persiapan
menghasilkan produk struktur protein yang akan
digunakan selama proses rekonstruksi jaringan.
Pada jaringan lunak yang normal (tanpa perlukaan),
pemaparan sel fibroblas sangat jarang dan biasanya
bersembunyi di matriks jaringan ikat. Sesudah
terjadi luka, fibroblas akan aktif bergerak dari
jaringan sekitar luka ke dalam daerah luka,
kemudian akan berproliferasi serta mengeluarkan
28
beberapa substansi (kolagen, elastin, hyaluronic acid,
fibronectin dan profeoglycans) yang berperan dalam
membangun jaringan baru. Akan terbentuk jaringan
granulasi berupa sel-sel dan pembuluh darah baru
yang tertanam di dalam jaringan. Selain itu juga
akan terjadi angiogenesis atau proses pembentukan
pembuluh kapiler baru di dalam luka (Falanga dan
Iwamoto, 2008). Setelah itu akan dimulai proses
selanjutnya yaitu epitelisasi. Keratinisasi akan
dimulai dari pinggir luka dan akhirnya membentuk
barier yang menutupi permukaan luka. Dengan
sintesis kolagen oleh fibroblas, pembentukan
lapisan dermis ini akan disempurnakan kualitasnya
dengan mengatur keseimbangan jaringan granulasi
dan dermis. Fase proliferasi akan berakhir jika
epitel dermis dan lapisan kolagen telah terbentuk
(Hoyt dkk, 2007).
Pada suatu penelitian menggunakan tikus putih,
dilaporkan bahwa tiga hari setelah perlukaan, luka
pada tikus putih sudah mulai mengalami pembentukan
29
jaringan granulasi yang diikuti dengan
reepitelisasi sehingga membuktikan fase perbaikan
luka terjadi secara tumpang tindih. Fibroplasia
pada luka juga meningkat pada hari ke lima sampai
ke tujuh (Kusmiati dkk, 2006). Fase selanjutnya
yaitu Fase remodelling yang dimulai sekitar minggu
kedua setelah perlukaan dan berakhir kurang lebih
12 bulan. Fibroblas sudah mulai meninggalkan
jaringan granulasi, warna kemerahan dari jaringan
mulai berkurang karena pembuluh mulai regresi dan
serat fibrin dari kolagen bertambah banyak untuk
memperkuat jaringan parut. Kekuatan dari jaringan
parut akan mencapai puncaknya pada minggu ke
sepuluh setelah perlukaan. Sintesis kolagen yang
telah dimulai sejak fase proliferasi akan dilanjutkan
pada fase maturasi. Kolagen muda (gelatinous collagen)
yang terbentuk pada fase proliferasi akan berubah
menjadi kolagen yang lebih matang, yaitu lebih
kuat dan struktur yang lebih baik (Sheid dkk,
2000). Luka dikatakan sembuh jika terjadi
kontinuitas lapisan kulit dan kekuatan jaringan
30
kulit mampu atau tidak mengganggu untuk melakukan
aktivitas yang normal. Meskipun proses penyembuhan
luka sama, namun outcome atau hasil yang dicapai
ternyata tidak sama dengan manusia, bahkan tidak
sama untuk masing-masing individu tikus putih. Hal
ini sangat tergantung dari kondisi biologik
masing-masing individu, lokasi serta luasnya luka
(Hoyt dkk, 2007).
2.4 Konsep Terapi Madu
2.4.1. Konsep Madu
Madu merupakan produk lebah yang lebih dahulu
dikenl dan diteliti. Madu terbuat dari nektar yang
dikumpulkan lebah madu dari berbagai tumbuhan
berbunga. Lebah akan menyimpan nektar di sarangnya
dalam bentuk madu sebagai makanan mereka sendiri.
Namun, para peternak lebah memanen madu yang
berlebihan dan menjualnya. Madu memilika efek
antibakteri sehingga banyak dipakai untuk mengobati
luka dan mempercepat penyembuhan (Suranto, 2007).
31
Madu adalah cairan manis alami berasal dari nektar
tumbuhan yang diproduksi oleh lebah madu. Lebah
madu mengumpulkan nektar madu dari bunga
mekar,cairan tumbuhan yang mengalir di dedaunan dan
kulit pohin, atau kadang-kadang dari embun. Nektar
adalah senyawa kompleks yang dihasilkan kelenjar
necteriffer dalam bunga, bentuknya berupa cairan,
berasa manis alami dengan aroma yang lembut
(Suranto, 2007).
2.4.2. Karakteristik Madu
Menurut Suranto (2007) madu mempunyai banyak
keunggulan karena karakteristiknya. Sepuluh
karakteristik fisis madu adalah sebagai berikut :
2.4.2.1 Kekentalan (viskositas)
Madu yang baru diekstrakan berbentuk cairan
kental. Kekentalannya tergantung dari komposisi
madu, terutama kandungan airnya. Bila suhu
meningkat, kekentalan madu akan menurun.
2.4.2.2 Kepadatan (densitas)
Madu mempunyai ciri khas yaitu kepadatannya akan
mengikuti gaya gravitasi sesuai berat jenis.
32
Bagian madu yang kaya akan air (densitasnya
rendah) akan berada diatas madu yang lebih padat
dan kental.
2.4.2.3 Sifat Menarik Air (higroskopis)
Madu bersifat menyerap air sehingga akan bertambah
encer dan akan menyerp kelembapan udara
sekitarnya.
2.4.2.4 Tegangan Permukaan (surface tension)
Madu memiliki tegangan permukaan yang rendah
sehingga sering digunakan sebagai campuran
kosmetik. Tegangan permukaan madu bervariasi
tergantung sumber nektarnya dan berhubungan dengan
kandungan zat koloid.
2.4.2.5 Suhu
Madu mempunyai sifat lambat menyerap suhu
lingkungan, tergantung dari komposisi dan derajat
pengkristalannya. Dengan sifat yang mampu
mengantarkan panas dan kekentalan yang tinggi
menyebabkan madu mudah mengalami overheating
(kelebihan panas) sehingga pengadukan dan
33
pemanasan madu haruslah dilakukan secara hati-
hati.
2.4.2.6 Warna
Warna madu bervariasi dari transparan hingga tidak
berwarna seperti air, dari warna terang hingga
hitam. Warna dasar madu adalah kuning kecoklatan
seperti gula caramel. Warna madu dipengaruhi oleh
sumber nektar, usia madu dan penyimpanan.
2.4.2.7 Aroma
Aroma madu yang khas disebabkan oleh kandungan zat
organiknya yang mudah menguap (volatil). Aroma madu
bersumber dari zat yang dihasilkan sel kelenjar
bunga yang bercampur dalam nektar dan juga karena
proses fermentasi dan gula, asam amino dan vitamin
selama pematangan madu.
2.4.2.8 Rasa
Rasa madu yang khas ditentukan oleh kandungan asam
organik dan karbohidratnya, juga dipengaruhi oleh
sumber nektarnya. Kebanyakan madu rasanya manis
dan agak asam.
2.4.2.9 Sifat Mengkristal
34
Madu cenderung mengkristal pada proses penyimpanan
di suhu kamar. Banyak orang berfikir bila madu
mengkrtistal berarti kwalitas madu buruk atau
sudah ditambah gula.
2.4.2.10 Memutar Optik
Madu memiliki kemampuan mengubah sudut putaran
cahaya terpolarisasi. Kemampuan ini disebabkan
kandungan zat gula yang spesifik dalam madu.
2.4.3. Komposisi Madu
Menurut Suranto (2007) komposisi madu bervariasi :
2.4.3.1 Gula
Komposisi terbesar madu adalah gula fruktosa dan
glukosa (85-95% dari total gula). Tingginya
kandunga gula sederhana dan presentasi fruktosa
menciptakan karakteristik nutrisi yang khas untuk
madu.
2.4.3.2 Air
35
Komposisi terbesar kedua setelah gula adalah air.
Keberadaan air dalam madu merupakan hal penting
terutama pada proses penyimpanan. Hanya madu
mengandung kadar air kurang dari 18% yang dapat
disimpan tanpa kwatir terjadi fermentasi.
2.4.3.3 Kalori
Madu merupakan salah satu nutrisi alami sumber
energi. Satu kilogram madu mengandung 3,280 kalori
atau setara dengan 50 buir telur ayam, 5,7 liter
susu, 25 buah pisang, 40 buah jeruk, 4 kilogram
kentang dan 1,68 kilogram daging.
2.4.3.4 Enzim
Enzim yang terkandung dalam madu adalah invertase,
diastase, katalase, oksidase, peroksidase, dan
protease. Guna enzim ini adalah memecah sukrosa
menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim diastase
berfungsi mengubah zat tepung menjadi dekstrin dan
maltosa. Kemampuan enzim mengubah zat tepung ini
dipengaruhi oleh suhu 60-80ºC. Enzim katalase
mengubah hydrogen peroksidase menimbulkan efek
antibakteri.
36
2.4.3.5 Hormon
Hormon adalah zat kimia yang berfungsi mengatur
aktivitas sel atau organ tubuh. Madu mengatur
hormon gonadotropin yang berfungsi menstimulasi
kelenjar seksual.
2.4.3.6 Asam amino
Madu mengandung asam amino ensensial yang penting
untuk tubuh seperti proline, tirosin, fenilalanin, glutamin
dan asam aspartat. Namun, kandungan sangat bervariasi
dari 0,6 hingga 500 mgdalam 100 gram madu.
2.4.3.7 Vitamin dan mineral
Madu kaya akan vitamin A, vitamin B kompleks
(lengkap), vitamin C, D, E dan K. Penelitian di
Universitas Florida Departemen Ilmu Makanan dan
Nutrisi penting seperti vitamin B6, riboflavin,
thiamin dan asam pantotenat. Madu mengandung
mineral cukup lemgkap namun bervariasi antara
0,01% - 0,64%, D. Jarvis meneliti kandungan
mineral madu dan memastikan dari 100% sampel
terdapat zat besi, kalium, kalsium, magnesium, tembaga,
mangan, natrium, dan fosfor. Zat lainnya adalah brium,
37
seng, sulfur, klorin, yodium, zirconium, gollium, vanadium, colbalt
dan molybdenum. Sebagian kecil madu ada yang
mengandung bismuth, germanium, lithium dan emas.
2.4.4. Penyimpanan Madu
Proses penyimpanan akan mempengaruhi kwalitas madu.
Untuk mempertahankan kwalitasnya, madu harus
disimpan dalam wadah kaca (lebih dipilih yang warna
gelap), keramik, porselin, kayu tertentu, atau
stainles stel. Pemggunakan wadah besi, tembaga,
timah, atau campuran logam harus dihindari karena
dapat bereaksi dengan gula dan asam organik madu
serta menghasilkan zat beracun.
Suhu yang ideal untuk menyimpan madu adalah sekitar
20ºC dengan kelembaban kurang dari 65%. Penyimpanan
di ats suhu 25ºC akan menurunkan kwalitas yang
disebabkan perubahan enzim dan kimiawi madu
(Suranto, 2007).
2.4.5. Cara membedakan madu murni dengan madu palsu:
1) Dibakar di atas sendok.
Taruhlah madu pada sebuah sendok logam. Bakar
38
bagian bawah sendok dengan api/lilin. Madu yang
asli akan mendidih hingga busanya tumpah dari
sendok, sedangkan yang palsu, meskipun mendidih
namun busa tak sampai tumpah.
2) Dengan kertas koran.
Teteskan madu pada kertas tipis/koran. Madu yang
asli tidak akan membuat kertas basah/robek.
Sedangkan madu palsu akan terserap ke dalam
kertas, karena kandungan airnya yang lebih
tinggi.
3) Menggunakan korek api.
Masukkan batang korek api ke dalam madu beberapa
saat. Ambil dan pantikkan/gesekkan agar menyala.
Bila madu asli, korek akan tetap bisa menyala,
dan sebaliknya.
4) Dengan segelas air.
Teteskan setetes madu ke dalam segelas air. Madu
asli akan langsung jatuh ke dasar gelas dan tetap
terlihat berkumpul/tidak larut dengan air.
39
5) Dimasukkan dalam freezer.
Masukkan madu ke dalam freezer/lemari es. Madu
asli tidak akan membeku.
6) Dicampur kuning telur.
Campur dan aduk madu dengan kuning telur bebek.
Bila madu asli, telur akan berubah warna dan
terlihat seperti setengah matang.
2.4.6. Pemanfaatan Madu Di Bidang Kesehatan
Menurut Suranto (2007) dalam dunia kesehatan,
pemanfaatan madu bukanlah hal yang asing. Ada
beberapa aturan yang harus diperhatikan jika anda
mengkonsumsi madu untuk tujuan pengobatan, yakni
perhatikan dosisi dan efek sampingnya.
2.4.5.1 Dosis
Dosis madu dianjurkan untuk orang dewasa adalah
100-200 gram sehari, diminum tiga kali sehari,
pagi sebanyak 30-60 gram, siang 40-80 gram, dan
malam 30-60 gram. Disarankan satu jam setengah
atau dua jam sebelum makan atau tiga jam sesudah
makan. Untuk anak-anak, dosis madu adalah 30 gram
sehari. Madu sebaiknya diminum dengan campuran air
40
agar lebih mudah dicerna dan mencapai peredaran
darah, ke jaringan, dan sel tubuh (Yoirish, 1959).
2.4.5.2 Efek Samping
American Journal of Clinical Nutrition tahun 1995
melaporkan konsumsi madu pada orang normal dapat
menimbulkan diare atau gangguan perut. Hal ini
mungkin disebabkan kandungan fruktosa madu cukup
tinggi. Kadar glukosa madu termasuk yang tertinggi
sekelompok buah apel dan pir (Dotinga, 2004).
Tingginya fruktosa madu pada beberapa orang dapat
menyebabkan gangguan penyerapan yang disebut
malarbsorpsi fruktosa. Hal ini cukup merepotkan
bagi orang-orang yang sebelumnya punya pencernaan
yang sensitif. Namun hal tersebut justru
menguntungkan untuk orang yang punya keluhan susah
buang air besar (Ladas, 1995).
2.4.5.3 Perawatan Luka dan Luka Bakar
Penggunaan madu untuk perawatan sudah banyak
dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu. Dunia
kedokteran modern saat ini telah banyak
membuktikan madu sebagai obat yang unggul
41
(Suranto, 2007). Sebuah laporan menunjukkan luka
yang dibalut dengan madu menutup pada 90 % kasus.
Pada luka bakar derajat ringan, penyembuhan dengan
olesan madu berlangsung lebih cepat. Pasien yang
luka bakar berat yang harus ditransplantasi kulit
dipercepat penyembuhannya dengan madu
(Subrahmanyam, 1991).
Penelitian yang dimuat di sebuah jurnal bedah
tahun 1991 menunjukan keunggulan madu
dibandingkan obat topikal Silver Sulfadiazin untuk luka
bakar. Sejumlah 104 wanita dan pria dengan
berbagai derajat luka bakar dibagi 2 kelompok.
Kelompok pertama mendapatkan balutan madu dan
kelompok kedua dibalut dengan obat topikal Silver
Sulfadiazin.
Tabel 2.3 Perbandingan Madu dan Silver Sulfadiazin
Kondisi Luka KelompokMadu
KelompokSilver
SulfadiazinJaringan tumbuh rata-rata
7,5 hari 13,4 hari
Luka tidak mengandungkuman
91% 7%
42
Kesembuhan 15,4 hari 17,2Keluhan nyeri danbekas luka
Lebihsedikit
Lebih banyak
(Subrahmanyam, 1991.Tropical Aplication of Honey inTreatment of Burns)
Madu merangsang terbentuknya kulit yang baru dan
sehat sehingga jarang membuat bekas luka yang
jelek. Kandungan madu yang kaya nutrisi membuat
pasokan zat-zat yang dibutuhkan penyembuhan luka
selalu cukup (Broadhurst, 2000).
Manfaat lainnya adalah madu dapat mengurangi
peradangan yang ditandai dengan berkurangnya
nyeri, bengkak, dan luka yang mengering. Salah
satu penyebabnya karena madu memiliki osmolaritas
yang tinggi hingga menyerap air dan memperbaiki
sirkulasi serta pertukaran udara di area luka.
Selain itu, madu memiliki efek membersihkan. Hal
ini dikarenakan madu bersifat lengket pada luka
dan jaringan mati turut terangkat hingga luka
menjadi bersih (Broadhurst, 2000).
43
Madu berkhasiat meningkatkan daya tahan tubuh
karena dapat meningkatkan jumlah sel darah putih.
Jadi, kemampuan madu untuk menghambat radikal
bebas akan mengurangi kerusakan jaringan, dan
kemampuannya merangsang sel darah putih akan
mempercepat penyembuhan. Madu juga membuat
lingkungan menjadi lembab yang mendukung
pembentukan kulit baru (Broadhurst, 2000).
2.4.5.4 Mengandung Antibiotika
Efek antibakteri madu pertama kali dikenal tahun
1892 oleh van Ketel. Awalnya, efek antibakteri ini
diduga karena kandungan gula madu yang tinggi,
yang disebut efek osmotik. Namun, penelitian lebih
lanjut menunjukkan adanya zat inhibine yang pada
akhirnya diidentifikasi sebagai hidrogen peroksida
yang berfungsi sebagi antibakteri (Suranto, 2007).
2.4.5.5 Efek Madu
1) Efek Osmotik
Madu terdiri dari campuran 84% gula dengan
kadar air sekitar 15-20% sehingga sangat tinggi
44
kadar gulanya. Sedikitnya kandungan air dan
interaksi air dengan gula tersebut akan membuat
bakteri tidak dapat hidup. Tidak ada bakteri
yang mampu hidup pada kadar air kurang dari 17%
(Molan PC, 2000).
Berdasarkan efek osmotik ini, seharusnya madu
yang diencerkan hingga kadar gulanya menurun
akan mengurangi efek antibakteri, namun,
kenyataannya, ketika madu dioleskan pada
permukaan luka yang basah dan tercampur dengan
cairan luka, efek antibakterinya tidak hilang.
Madu tetap dapat mematikan bakteri meskipun
diencerkan hingga 7-14 kali. Dengan demikian,
disimpulkan ada faktor lain yang menunjang efek
antibiotika madu (Suranto, 2007).
2) Aktivitas Hidrogen Peroksida
Madu juga mengandung zat lain yang dapat
membunuh bakteri yaitu hidrogen peroksida. Kelenjar
hipofaring lebah madu mensekresikan enzim glukosa
oksidase yang akan bereaksi dengan glukosa bila
45
ada air dan memproduksi hidrogen peroksida. Reaksi
kimiawi ini berlangsung sesaat, tetapi dalam
jumlah kecil terus terbentuk hingga madu
matang. Bila madu bereaksi kembali dengan air
maka produksi hidrogen peroksida akan meningkat
lagi. Konsentrasi hidrogen peroksida pada madu
sekitar 1 mmol/l, 1000 kali lebih kecil
jumlahnya daripada larutan hidrogen peroksida
3% yang biasa dipakai sebagai antiseptik. Meski
konsentrasinya lebih kecil, efektivitasnya
tetap baik sebagai pembunuh kuman. Efek samping
hidrogen peroksida seperti merusak jaringan
akan diatasi madu dengan zat antioksidan dan
enzim-enzim lainnya (Suranto, 2007)
3) Sifat Asam Madu
Ciri khas madu lainnya adalah bersifat asam
dengan pH antara 3,2-4,5, cukup rendah untuk
menghambat pertumbuhan bakteri yang berkembang
biak rata-rata pada pH 7,2-7,4 (Suranto, 2007).
4) Faktor Fitokimia
46
Pada beberapa jenis madu juga ditemukan zat
antibiotik. Zat tersebut disebut faktor non-
peroksida. Madu selama ini telah memiliki
faktor tersebut adalah madu manuka (Leptospermum
scoparium) berasal dari Selandia Baru. Di
Australia, madu dari spesies Leptospermum yang
lain, jellybush, juga ditenggarai memiliki zat
non-peoksida ini (Suranto, 2007).
5) Aktifitas Fagositosis dan Meningkatkan Limfoit
Fagositosis adalah mekanisme membunuh kuman
oleh sel yang disebut fagosit, sedangkan limfosit
adalah sel darah putih yang terbesar perannya
dalam mengusir kuman. Penelitian terbaru
memperlihatkan madu dapat meningkatkan
pembelahan sel limfosit, artinya turut memperbanyak
pasukan sel darah putih tubuh. Selain itu, madu
juga meningkatkan produksi sel monosit yang
dapat mengeluarkan sitokin, TNF-alfa, interleukin 1,
dan interleukin 6 yang mengaktifkan respon daya
47
tahan tubuh terhadap infeksi. Kandungan glukosa
dan keasaman madu juga secara sinergis ikut
membantu sel fagosit dalam menghancurkan bakteri
(Suranto, 2007).
Beberapa hal yang membuat efek antibakteri madu
berbeda-beda adalah kandungan hidrogen
peroksida dan non-peroksida, seperti vitamin C,
ion logam, enzim katalase, dan juga ketahanan
madu terhadap suhu dan sensitifitas enzimnya
terhadap cahaya. Pada dasarnya, semua madu asli
mempunyai sifat antibakteri karena kadar
gulanya yang tinggi. Beberapa ahli berpendapat,
efek antibakteri madu secara umum memang akan
berkurang bila madu bercampur atau diencerkan.
Efek madu sebagai antibakteri terbaik diperoleh
dari penggunaan topikal (dioleskan) (Suranto,
2007)
2.4.7. Penggunaan Madu Sebagai Kompres Luka
Madu yang bersifat asam dapat memberikan lingkungan
asam pada luka sehingga akan dapat mencegah bakteri
48
melakukan penetrasi dan kolonisasi. Selain itu
kandungan air yang terdapat dalam madu akan
memberikan kelembaban pada luka. Hal ini sesuai
dengan prinsip perawatan luka modern yaitu ‘‘Moisture
Balance’’. Hasil penelitian Gethin GT et al (2008)
melaporkan madu dapaat menurunkan Ph dan mengurangi
ukuran luka kronis (ulkus vena/arteri dan luka
dekubitus) dalam waktu du minggu secara signifikan.
Hal ini akan memudahkan terjadinya prses granulasi
dan eitelisasi pada luka.
Efem (1993) meneliti kemampuan madu sebagai
penyembuhan luka akibat gangrene, dan luka akibat
diabetes mellitus pada pasien di Afrika. Madu
diberikan secara topika sebanyak 15-30 ml sekali
sehari. Luka gangrene dan luka diabetic sembuh dan
membaik diikuti dengan tidak ditemukannya bakteri-
bakteri yang sebelumnya ada di sekitar luka, yakni
P.pyocyenea, E.coli, S.aureus, P.mirabilitas, coliform. Klebsiella,
Sterptococcus faecalis, dan Streptococcus pyogenes.
49
Luka setelah operasi cesar juga tak luput dari
penelitian para ahli dan dipublikasikan dalam
Australia NZ Journal of Obstetrics & Gynaecology. Madu
diaplikasikan dengan perban pada luka bekas
operasi. Ditemukan kemampuan madu sebagai
penyembuhan luka bekas operasi Caesar akan membuka
peluang penggunaan madu dalam klinik.