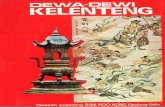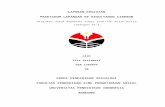GAMBARAN PENGHAYATAN PERAN IBU DALAM SOSIALISASI IDENTITAS GENDER ANAK PEREMPUAN KELUARGA TIONGHOA
Akulturasi Budaya Tionghoa dan Cirebon di Kesultanan ... - OSF
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Akulturasi Budaya Tionghoa dan Cirebon di Kesultanan ... - OSF
AKULTURASI BUDAYA TIONGHOA DAN CIREBON
DI KESULTANAN CIREBON
Disertasi
Diajukan kepada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Doktor
dalam Bidang Sejarah dan Peradaban Islam
Oleh:
Mukhoyyaroh
(31171200000017)
Promotor:
Prof. Dr. Didin Saepudin, M.A.
Prof. Dr. M. Ikhsan Tanggok, M.Si
Program Studi Pengkajian Islam
Konsentrasi Sejarah dan Peradaban Islam
Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
2021 M/1442 H
ii
Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengungkap dan menganalisis aktivitas sosial-budaya, dan relasi
sosial budaya, serta makna simbolik dan filosofis dari wujud budaya Tionghoa dan budaya
Cirebon di Kesultanan Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan
termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan dan lapangan, sedangkan prosedur
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan pencatatan, serta
dokumentasi. Sementara pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan historis,
antropologis dan semiotik. Adapun sumber yang digunakan adalah sumber primer dan
sekunder yang terdiri dari sumber tulisan berupa buku, artikel jurnal, dan arsip, serta sumber
non-tulisan berupa hasil wawancara dan bukti arkeologis. Temuan penting penelitian ini,
yaitu: Pertama, kontak sosial-budaya etnis Tionghoa dengan masyarakat Cirebon terjadi
melalui tiga gelombang, yaitu dimulai sejak abad ke-15, yang ditandai dengan kedatangan
Cheng Ho dan para pasukannya; Gelombang kedua terjadi pada akhir abad ke-15, yang
ditandai dengan kedatangan Puteri Tiongkok bernama Ong Tien Nio dengan seluruh barang
bawaannya; Gelombang ketiga terjadi di abad ke-18, ditandai dengan masuknya orang-orang
Tionghoa sebagai orang-orang pelarian dari Batavia. Kedua, relasi sosial-budaya etnis
Tionghoa dan masyarakat Cirebon yang kemudian menghasilkan akulturasi budaya. Budaya
Cirebon dan budaya Tionghoa yang telah terakulturasi dalam perkembangannya sangat
dipengaruhi oleh agama Islam. Ketiga, berbagai bukti arkeologis seperti Gapura Siti Inggil,
Makam Astana Gunung Jati dan Guha Sunyaragi serta Kereta Kencana Singa Barong dan
Batik, semuanya mendapat pengaruh dari Hindu, Tiongkok dan Belanda, serta memiliki
makna simbolik dan filosofis yang berbeda-beda. Lewat arsitektur dan simbol-simbol yang
ada menunjukkan betapa Kesultanan Cirebon sarat dengan nilai-nilai ketauhidan yang
ditemukan pada dua puluh tiang Mande Malang Semirang. Kesultanan Cirebon sekalipun
merupakan Kesultanan Islam, tetapi sangat inklusif terhadap dinamika masyarakat dan ragam
budaya yang datang dari luar, serta berdiri di atas keberagaman budaya dan meletakkan
penghormatan yang tinggi terhadap keyakinan orang lain. Hal tersebut mengakibatkan
terjadinya akulturasi, khususnya antara kebudayaan Tionghoa dan budaya Cirebon di
Kesultanan Cirebon. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya
Tionghoa dan budaya Cirebon di Kesultanan Cirebon menyatu dalam bentuk akulturasi,
bukan asimilasi ataupun difusi.
Kata kunci: Akulturasi, budaya Tionghoa, budaya Cirebon, Kesultanan Cirebon
iii
ملخص
رذف ز اذساعخ إ اىشف ازس١ شبط االخزبػ اثمبف، افىشح اثمبف١خ، اؼ اشض افغف اثمبفخ
اذساعبد اىزج١خ اص١١خ اثمبفخ ازش١ش٠ج١خ ف عطخ ازش١ش٠ج. اعزخذذ اجبزثخ اح اى١ف ز اذساعخ
ا١ذا١خ. ثبغجخ طش٠مخ خغ اج١ببد، لبذ اجبزثخ ثبالزظخ، اساس، ازغد١، ازث١ك. ثبغجخ مبسثخ،
ثبغجخ صذس، ف١مغ إ اصذس األعبع اعزخذذ اجبزثخ امبسثخ ازبس٠خ١خ األزشثخ١خ، اغ١١خ١خ.
وزت دس٠بد ثبئك، صبدس غ١ش وزبث١خ ث اساس ا٢ثبس ازبس٠خ١خ. ازبئح ابخ ز اثب ٠زى
االرصبي االخزبػ اثمبف ث١ اص١١١ ادزغ ازش١ش٠ج زص ف ثالس خبد، ثذأ إ -أوالاذساعخ ب ٠:
ظ ػشش بخامش ااخش. اخخ اثب١خ لؼذ ف ( خ١شCheng Ho امش اخبظ ػشش، ثد١ئ رش١ح )
( غ و ب ززب األش١بء. اخخ اثبثخ زصذ ف Ong Tien Nioثد١ئ أ١شح ص١١خ ادػذ أح ر١ ١ )
١خ إ اؼاللخ االخزبػ١خ اثمبف١خ اص١ -ثانيا(. Bataviaامش اثب ػشش، ثد١ئ اص١١١ االخئ١ ثبربف١ب )
. إ اثمبفخ ازش١ش٠ج١خ اص١١خ از رثبلفذ ف رطسب رأثشد وث١شا ثبذ٠ ازش١ش٠ج١خ رزح ش١ئب ازثبلف
(، ضش٠ر Gapura Siti Inggilإ اؼذ٠ذ اجشا١ األثش٠خ ازبس٠خ١خ ث ثاثخ ع١ز إد١ ) -ثالثااإلعال.
( ػشثخ ى١خ Guha Sunyaragi(، خب ع١بساخ )Makam Astana Gunung Jatiأعزبب خح خبر )
(، ثبر١ه )ف سع رم١ذ ػ امبػ(، وب رأثشد ثب١ذع١خ، االذ٠خ، singa barongع١دب ثبسح )
عطخ اشص، خذب اإلشبساد إ أ ذعخ اؼبس٠خ خالي ااص١١خ، ف١ب ؼب سض٠خ فغف١خ خزفخ.
Mandeازش١ش٠ج ب صجغخ ل١ ازز١ذ ل٠خ، خذبب ف ػشش٠ ػدا ع١ذ ثأػذح بذ بالح ع١١شاح )
Malang Semirang إ عطخ رش١ش٠ج ثبشغ أب إعال١خ، إال أب شزشوخ ف ازغ١١شاد االخزبػ١خ رأثشد .)
ذ ػ رع اثمبفبد سذ اغطخ رمذ٠شا ػب١ب ؼزمبد ابط. أد ثخزف اثمبفبد از خبءد اخبسج، لب
ره إ ازثبلف، ثخ ازسذ٠ذ ث١ اثمبفخ اص١١خ اثمبفخ ازش١ش٠ج٠خ ف عطخ ازش١ش٠ج. ثزا، رمي ز اذساعخ
(، ال asimilasiزثبلف ١ظ االعز١ؼبة )إ اثمبفخ اص١١خ اثمبفخ ازش١ش٠ج١خ ف عطخ رش١ش٠ج ارسذد ف شى ا
(.difusi) ازؼش٠ف
ازثبلف، اثمبفخ اص١١خ، اثمبفخ ازش١ش٠ج١خ، اغطخ ازش١ش٠ج١خ الكلمات المفتاحية:
iv
Abstract
This study aims to reveal and analyse the socio-cultural activities, cultural concepts, as well
as symbolic and philosophical meanings on the forms of Tionghoa culture and Cirebon
culture in the Cirebon Sultanate. The research method applied is the qualitative and belongs
to the type of literature and field research, while the data collection procedure is carried out
through observation, interviews, and recording, and documentation. Meanwhile, the research
approaches used are historical, anthropological and semiotic approaches. The sources used
are primary and secondary sources consisting of written sources in the form of books, journal
articles and archives, as well as non-written sources in the form of interviews and
archaeological evidence. The essential findings of this research are: First, the socio-cultural
contact of the Tionghoa ethnics with the Cirebon people occurred through three waves,
starting in the 15th century, which was marked by the arrival of Cheng Ho and his troops;
The second wave happened in the end of the 15th century, which was marked by the arrival
of a Tiongkok princess named Ong Tien Nio with all her belongings; The third wave
occurred in the 18th century, marked by the entry of Tiongkok people as refugees from
Batavia. Second, the socio-cultural relations of the Chinese ethnics and the Cirebon people
which later resulted in cultural acculturation. Furthermore, Cirebon culture and Tionghoa
culture which have been acculturated in their development are strongly influenced by Islam.
Third, various archaeological evidences, such as the Siti Inggil Gate, the Tomb of Astana
Gunung Jati and Guha Sunyaragi as well as the Singa Barong Golden Chariot and Batik, all
of which were influenced by Hinduism, the Netherlands and Tiongkok, had different
symbolic and philosophical meanings. Moreover, the architecture and symbols show how the
Cirebon Sultanate is full of monotheistic values found on the twenty Mande Malang
Semirang pillars. Even though the Sultanate of Cirebon is an Islamic Sultanate, it
implemented very inclusive on the dynamics of society and various cultures that came from
outside, and stood on cultural diversity, as well as placed high respect on the beliefs of
others. This resulted in acculturation, especially between Tionghoa culture and Cirebon
culture in the Cirebon Sultanate. Thus, this study concludes that Tionghoa culture and
Cirebon culture in the Cirebon Sultanate are united in the form of acculturation, instead of
assimilation or diffusion.
Keywords: Acculturation, Tionghoa culture, Cirebon culture, Cirebon Sultanate
v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
A. Konsonan
B. Vocal
1. Vocal Tunggal
Tanda Nama Huruf
Latin
Nama
Fathah a A
Kasrah i I
Dhammah u U
2. Vocal Rangkap
Tanda Nama Gabungan
Huruf
Nama
Fathah a A
Kasrah i I
Contoh:
H{aul : زي H{usain : زغ١
C. Ta’ Marbut}ah
Transliterasi ta‟ marbut}ah ditulis dengan “ha”, baik dirangkai dengan
b = ة
t = د
th = س
j = ج
h{ = ذ
kh = ش
d = د
dz = ر
r = س
z = ص
s = ط
sh = ػ
s} = ص
d} = ض
t} = ط
z = ظ
ع = „
g = ؽ
f = ف
q = ق
k = ن
l = ي
m =
n =
w =
h =
y =
vi
kata sesudahnya maupun tidak, contoh (شأح), madrasah (ذسعخ)
Contoh:
al-Madi>nah al-Munawwarah :اذ٠خ اسح
D. Shadda>h
Shaddah atau tashdid ditransliterasi, dilambangkan dengan huruf, yaitu
huruf yang sama dengan huruf yang bershaddah tersebut.
Contoh:
<Rabbana : سثب
Nazzala : ضي
E. Kata Sandang
Kata sandang “اي” dilambangkan berdasar huruf yang mengikutinya, jika
diikuti huruf syamsiyah maka ditulis sesuai huruf yang bersangkutan, dan
ditulis “al” jika diikuti dengan huruf qamariyah. Selanjutnya “اي” ditulis
lengkap baik menghadapi al-Qamariyah contoh kata al-Qamar (امش)
maupun al-Syamsiyah seperti kata al-Rajulu (اشخ).
Contoh:
al-Qalam : ام al-Syams : اشظ
F. Pengecualian Transliterasi
Pengecualian transliterasi adalah kata-kata bahasa Arab yang telah lazim
digunakan di dalam bahasa Indonesia dan menjadi bagian dalam bahasa
Indonesia, seperti lafal هللا, Asmaul Husna dan Ibn, kecuali
menghadirkannya dalam konteks aslinya dan dengan pertimbangan
konsistensi dalam penulis.
vii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat,
taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya.
Atas izin dan kuasa Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan
disertasi yang berjudul “Akulturasi Budaya Tionghoa dan Budaya Cirebon di
Kesultanan Cirebon”. Penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini masih jauh
dari kata sempurna. Namun, terlepas dari semua kekurangan yang ada, penulis
secara pribadi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua
pihak yang turut andil memberikan dukungan, baik moril maupun materil,
sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan.
Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus dan penuh hormat, penulis
sampaikan kepada Rektor UIN Syarif Hidayutllah Jakarta Prof. Dr. Hj. Amany
Burhanuddin Umar Lubis, Lc., M.A., beserta jajarannya, Direktur Sekolah
Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. H. Asep Saefudin Jahar,
M.Phil. Begitu pula halnya kepada Dr. H. Hamka Hasan, Lc., MA selaku Wakil
Direktur, Prof. Dr. H. Didin Saepudin, MA selaku Ketua Program Studi Doktor
dan H. Arif Zamhari, M.Ag., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Sekolah
Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya juga disampaikan
kepada Prof. Dr. H. Didin Saepudin, MA dan Prof. Dr. H. M. Ikhsan Tanggok,
M.Si selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan
bimbingan, arahan, petunjuk, saran dan kritik membangun secara kontinue kepada
penulis sehingga penyusunan disertasi ini bisa sampai pada ujian pendahuluan.
Kesediaan kedua pembimbing dalam melakukan sharing dan berdiskusi secara
langsung tentang konsep yang dibahas dalam disertasi ini mempermudah penulis
dalam menuangkan pikiran secara sistematis dan terarah sehingga menghasilkan
tulisan ini meski masih ditemukan banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi.
Penulis juga tidak lupa sampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh
Civitas Akademika Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mulai
dari para dosen yang telah melakukan tranformasi ilmu kepada penulis sehingga
menjadi bekal yang baik dalam memperkuat konsep keilmuan dan aplikasinya.
Juga kepada seluruh Pegawai dan Staf Sekretariat dan Staf Pepustakaan Sekolah
Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dengan penuh dedikasi
mereka melayani mahasiswa dengan ikhlas dalam menyiapkan berbagai
kebutuhan dan fasilitas yang dibutuhkan sehingga penyelesaian disertasi ini
berjalan secara berkesinambungan.
Kepada orang tua penulis ayahanda H. Mahsus dan Ibunda H. Rohmah,
terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan atas jasa, support dan doa yang
tiada henti-hentinya, serta limpahan kasih sayangnya. Juga ucapan terima kasih
kepada adik-adikku dan keluarga besar H. Amir yang telah memberikan
dukungan, do‟a, dan kasih sayangnya, sehingga dapat menjadi spirit dan motivasi
bagi penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Kepada anak-anakku tersayang,
Nadia Ashfia Zahra, Hasymi Naseem Al-Farabi, dan Atiya Azkia Zahra yang
dengan tulus selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayangnya
viii
sehingga studi ini bisa selesai. mohon maaf sayang, bunda tidak bisa selalu
mendampingi dan menemani kalian. Berkat motivasi dari merekalah, penulis
dengan segala tantangan dan lika-liku hidup yang dihadapi, utamanya dalam
menyusun disertasi ini, bisa terselesaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan
balasan yang setimpal kepada kita, sehingga kesuksesan selalu menyertai kita
semua.
Penulis juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya
kepada Kementrian Agama selaku pemberi beasiswa tahun 2017-2020, sehingga
dapat mengikuti pembelajaran dan menyelesaikan program doktor di SPS UIN
Jakarta. Juga kepada ketua Yayasan Sasmita Jaya Group, Rektor Universitas
Pamulang beserta jajarannya, Dekan Fakultas Sastra dan Ketua Prodi Sastra
Inggris atas support dan kesempatan yang diberikan, sehingga penulis dapat
menyelesaikan studi program Doktor di UIN Syarif Hidayatullah.
Terima kasih juga penulis sampaikan kepada pamanda Dr. H. Masduki, Dr.
Imam Syafii, Kyai Ahmad Rusydi atas support dan perhatiannya. buat teman-
teman angkatan 2017 program doctor, teman-teman dosen UNPAM/STMIK
Eresha, teman-teman Persada Nusantara, dan teman-teman DPW Adpisi DKI,
support, perhatian, kasih sayang, persaudaraan dan kebersamaan yang selama ini
terjalin menjadi energi tersendiri buat penulis. Kepada adinda Sabil Mokodenseho
dan Yunus yang telah banyak membantu penulis dalam setiap kesulitan, baik
kesulitan dalam bidang akademik maupun kesulitan-kesulitan lainnya,
jazakumullah khoirol jaza….
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para informan; Dr. Opan,
Bapak Permadi S.H., Drh. Bambang Irianto, Bapak Ajat, Bapak Hafidz, dan
Bapak Jazuli, yang telah banyak membantu dan bersedia untuk meluangkan
waktunya di sela-sela pekerjaan untuk membantu penulis dalam melakukan
penelitian di Kesultanan Cirebon.
Akhirnya, penulis sadar bahwa dalam penulisan disertasi ini masih banyak
kekurangan, kekeliruan, dan kealfaan dalam berbagai aspek sehingga mengurangi
kebulatan dan keutuhan isi serta kandungan disertasi ini di mata pembaca. Oleh
karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif
untuk memperbaiki dan menyempurnakan disertasi ini. Semoga Allah SWT selalu
menyertai langkah amal usaha kita dengan rahmat dan hidayahnya. Amin Ya
Rabbal Alamin.
Jakarta, 05 Januari 2021
Penulis,
Mukhoyyaroh
ix
DAFTAR ISI
Halaman Judul ............................................................................................................ i
Abstrak ........................................................................................................................ ii
Pedoman Transliterasi Arab Latin ............................................................................ v
Kata Pengantar ............................................................................................................ vii
Daftar Isi ...................................................................................................................... ix
Daftar Gambar ............................................................................................................ xi
Daftar Singkatan ......................................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1
B. Pemasalahan .................................................................................... 18
1. Identifikasi Masalah .................................................................. 18
2. Perumusan Masalah ................................................................... 19
3. Pembatasan Masalah ................................................................. 19
C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 19
D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian ................................................ 20
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan ................................................. 20
F. Metode Penelitian ............................................................................ 27
G. Sistematika Penulisan ...................................................................... 30
BAB II INTERAKSI BUDAYA: TIONGHOA, NUSANTARA
DAN ISLAM ............................................................................................. 31
A. Konsep Kebudayaan: Akulturasi, Asimilasi dan
Difusi ............................................................................................... 31
B. Kedatangan Etnis Tionghoa: Jejak Cheng Ho dan
Muslim Tionghoa ............................................................................ 55
C. Pra Kolonial: Muslim Tionghoa sebagai Budaya
Hibrida ............................................................................................. 61
D. Era Kolonial Belanda: Kemunduran Budaya Muslim
Tionghoa-Jawa ................................................................................ 65
BAB III SEJARAH KESULTANAN CIREBON ................................................ 69
A. Profil dan Dialektika Kesultanan .................................................... 69
1. Kesultanan Cirebon ................................................................... 69
2. Dialektika Politik dan Islam ...................................................... 75
B. Perkembangan Daerah dan Masyarakat Cirebon ............................ 87
1. Daerah Cirebon .......................................................................... 87
2. Cirebon dalam Lintas Dagang ................................................... 93
3. Cirebon sebagai Basis Syiar Islam ............................................ 98
C. Masuknya Etnis Tionghoa Ke Cirebon ........................................... 105
x
BAB IV RELASI SOSIAL-BUDAYA ETNIS TIONGHOA DAN
MASYARAKAT CIREBON ...................................................... 113
A. Mengenal Budaya Cirebon .............................................................. 113
B. Corak Budaya Tionghoa .................................................................. 118
C. Pergumulan Budaya Tionghoa dan Budaya Cirebon ...................... 129
BAB V BUDAYA TIONGHOA DAN CIREBON DI
KESULTANAN CIREBON: MAKNA SIMBOLIK DAN
FILOSOFIS .......................................................................................... 141
A. Arsitektur Keraton Kasepuhan ........................................................ 143
B. Kereta Kencana Singa Barong ........................................................ 175
C. Batik Cirebon .................................................................................. 188
D. Guha Sunyaragi ............................................................................... 203
BAB VI PENUTUP....................................................................................... 211
A. Kesimpulan ...................................................................................... 211
B. Saran dan Rekomendasi .................................................................. 212
Daftar Pustaka ............................................................................................................... 213
Glosarium ..................................................................................................................... 249
Indeks ............................................................................................................................ 253
Biografi Penulis ............................................................................................................
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. : Kebudayaan A dan Kebudayaan B bertemu dalam
Masyarakat, sehingga menghasilkan suatu kebuadayaan
baru (A+B) 50
Gambar 2. : Pembauran dua unsur sosial yang berbeda dan
menghasilkan suatu unsur yang baru 50
Gambar 3. : Pembaruan dua unsur sosial yang berbeda akan
menghasilkan suatu ukuran yang baru 50
Gambar 4. : Struktur Kosmologi Keraton Kasepuhan 145
Gambar 5. : Siti Inggil 146
Gambar 6. : Mande Malang Semirang 156
Gambar 7. : Mande Semar Tinandu 158
Gambar 8. : Mande Pandawa Lima 161
Gambar 9. : Mande Pelinggihan (Pengiring) 165
Gambar 10. : Mande Karesmen 168
Gambar 11. : Tangga Masuk ke Makam Sunan Gunung Jati 170
Gambar 12. : Bagian Depan Tembok Makam Sunan Gunung Jati 173
Gambar 13. : Tembok Depan Makam Astana Gunung Jati 174
Gambar 14. : Kereta Kencana Singa Barong 177
Gambar 15. : Motif Wadasan Mega Mendung 195
Gambar 16. : Motif Sulur Mega Mendung 195
Gambar 17. : Motif Balong Teratai 198
Gambar 18. : Motif Piring Selampad 199
Gambar 19. : Motif Barongsai 202
Gambar 20. : Guha Sunyaragi (Guha Peteng) 205
Gambar 21. : Guha Sunyaragi (Bahan Dasar Batu Karang) 209
xii
DAFTAR SINGKATAN
ANRI : Arsip Nasional Republik Indonesia
KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi
PITI : Persatuan Islam Tionghoa Indonesia
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKI Partai Kumunis
SAW : Shollallahu Alaihi Wasallam
SDI : Sarekat Dagang Islam
SI : Sarkat Islam
SWT : Subhanahu Wa Ta’ala
UUD 1945 : Undang-Undang Dasar 1945
VOC : Vereenigde Oost-Indische Compagnie
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Keberadaan etnis Tionghoa1 di Indonesia merupakan persoalan yang sangat
menarik dan belum tuntas sampai saat ini. Suryadinata mengatakan masalah etnis
Tionghoa adalah masalah yang rumit, seperti persoalan ekonomi dan politik luar
negeri.2 Karena masalahnya begitu kompleks dan rentang waktunya yang cukup
panjang membuat persoalan yang bersifat historis, kultural, politis dan ekonomis3
menjadi tumpang tindih.
Jauh sebelum kedatangan bangsa Barat di Nusantara, etnis Tionghoa sudah
melakukan aktivitas perdagangan di Asia Tenggara4 termasuk Indonesia sejak abad
ke-16 dan awal abad ke-17. Mereka menukarkan barang-barang asal Tiongkok
seperti sutra dan porselen, rempah-rempah, obat-obatan dan barang-barang yang
langka dari kawasan Asia Tenggara.5 Fakta ini dipertegas oleh Azra bahwa
hubungan antara Nusantara dan etnis Tionghoa telah ada sejak pra Islam. Hubungan
itu telah meninggalkan banyak warisan penting dan jejak sejarah di negeri ini.6
Literatur yang berbicara tentang hubungan Indonesia dengan etnis Tionghoa
memang sangat terbatas,7 sehingga awal kedatangan etnis Tionghoa ke Nusantara
belum dapat dipastikan dengan jelas. Ada yang mengatakan telah terjadi kontak
1Dalam disertasi ini, sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2014 tentang
pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967
tanggal 28 Juni 1967, yang terkait dengan etnis menggunakan kata “Tionghoa”, sedangkan
kata “Tiongkok” digunakan untuk menyebut nama negara. Adapun penggunaan kata “Cina”
digunakan pada kutipan langsung maupun sumber kutipan. 2L. Suryadinata, Negara dan Etnis Tionghoa; Kasus Indonesia, (Indonesia: Pustaka
LP3S, 2002), h. 18. 3C. Setijadi, Ethnic Chinese in contemporary Indonesia: Changing Identity Politics
and the Paradox of Sinification, (Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2016), h. 1-11. 4X. Gong, “The Belt & Road Initiative and China‟s influence in Southeast Asia”. The
Pacific Review, vol. 32, no. 4, 2019, h. 635-665.; S. N. Lestari & N. S. Wiratama, “The dark
side of the Lasem maritime industry: Chinese power in opium business in the XIX
century”. Journal of Maritime Studies and National Integration, vol. 2, no. 2, 2018, h. 91-
100.; L. Y. Lim, “Southeast Asian Chinese business: Past success, recent crisis and future
evolution”. Business, Government and Labor: Essays on Economic Development in
Singapore and Southeast Asia, 2017, h. 313. 5B. Wiryomartono, “Urbanism and Ethnic Minority: Chinese Quarters and Society in
Jakarta-Indonesia 1600–Present”. In Traditions and Transformations of Habitation in
Indonesia, (Singapore: Springer, 2020), h. 105-127.; M. S. Heidhues, “Studying the Chinese
in Indonesia: A long half-century”. SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast
Asia, vol. 32, no. 3, 2017, h. 601-633. 6Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad
XVII-XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia, (Bandung:
Mizan, 1994), h. 11.; Azyumardi Azra, Jaringan UlamaTimur Tengah dan Kepulauan
Nusantara abad XVII dan XVIII, cet. IV, (Bandung: Mizan, 1998), h. 38-43. 7M. I. Tanggok, Menghidupkan Kembali Jalur Sutra Baru: Format Baru Hubungan
Islam Indonesia dan Cina, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), h. 10.
2
dengan etnis Tionghoa dari Dinasti Chou sejak 300 tahun SM. dengan bukti sejarah
berupa elemen kebudayaan seperti dalam kehidupan sosial kultural orang Dayak di
Kalimantan dan masyarakat Ngada di pulau Flores.8 Kemudian, ada temuan benda
pra sejarah seperti kapak dan sepatu di Tiongkok, Siberia dan Eropa Timur.9
Berdasarkan cerita dalam Dinasti Han, pemerintahan Kaisar Wan Ming (1-6 SM)
telah mengenal Nusantara dengan sebutan Huang Tse.10
Vleming menyatakan kontak antara Tionghoa-Indonesia terutama Jawa baru
terjadi awal abad ke-5 M ditandai dengan datangnya seorang pendeta Buddha dari
Tiongkok bernama Fa Hian. Sekitar tahun 413, Fa Hian singgah di Jawa selama
lima bulan dalam perjalanannya ke India. Berdasarkan catatannya, saat itu belum
ada etnis Tionghoa yang menetap di Jawa.11
Kemudian sekitar tahun 671, pendeta
Buddha lainnya yang bernama I-Tsing berangkat dari Canton menuju Nalanda
melalui Sriwijaya, dan menetap di daerah ini selama empat belas tahun.12
Dalam
tulisannya, I-Tsing bercerita tentang adat istiadat serta kejadian yang terjadi di
Sriwijaya.13
Ia juga menceritakan bahwa Raja Sriwijaya menyerahkan hasil-hasil
bumi kepada Maharaja Tiongkok. Bahkan, pada tahun 991, beberapa utusan
Sriwijaya pergi ke Tiongkok dan menetap setahun lamanya di Canton.14
Tidak
heran jika di tahun 1129, Maharaja Tiongkok memberikan gelar raja kepada
penguasa Jawa tersebut. Namun, pengiriman upeti itu seharusnya tidak boleh
dipandang sebagai bukti ketundukan yang satu kepada yang lain sebagaimana Cator
mengatakan bahwa harus ditunjukkan secara garis besar, pengiriman upeti mungkin
pada akhirnya tidak dianggap sebagai bukti konklusif dari keberadaan hubungan
bawahan dalam arti politik.15
Pasca abad ke-8, banyak pedagang Tionghoa yang bertolak ke daerah-daerah
bagian selatan Nusantara untuk mengunjungi pelabuhan Sriwijaya dan pelabuhan
Melayu. Pada tahun 1082, pemerintahan Yuan-Fong, Sung-Hui-Yao mengatakan
bahwa wakil kepala pengangkutan dan wakil kepala urusan dagang menerima surat
dari wakil umum pedagang asing di negara-negara di laut selatan yang ditulis dalam
bahasa Tiongkok. Surat itu berasal dari raja Chan-pei (Jambi), bagian dari San-Fo-
8R. Ratnawati, I. Syah, & S. Arif, “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang
Dwikewarganegaraan Etnis Tionghoa pada Masa Demokrasi Liberal”. Jurnal Pendidikan
dan Penelitian Sejarah, vo. 1, no. 1, 2013, h. 1-8. 9R. Maulana, “Dakwah dan Etnisitas: Negosiasi Identitas pada Majalah Cheng
Hoo”. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, vol. 19, no. 1, 2013, h. 25-39. 10
M. Taneo, F. A. Ndoen & S. Y. Neolaka, “History of Arrival and Development of
Chinese Ethnic in Kupang”. International Journal of Multicultural and Multireligious
Understanding, vol. 6, no. 5, 2019, h. 356-369.; B. G. Setiono, Tionghoa dalam Pusaran
Politik, (Jakarta: Trans Media, 2008), h. 20. 11
Hari Poerwanto, Orang Cina Khek dari Singkawang, (Depok: Komunitas Bambu), h.
39. 12
Slamet Mulyana, Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara
Islam di Nusantara, (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2007), h. 81-82. 13
Setiono, Tionghoa dalam Pusaran..., h. 21. 14
Mulyana, Runtuhnya Kerajaan Hindu…, h. 81. 15
W. J. Cator, The Economic Position of the Chinese in the Netherlands Indies,
(Oxford: 1936), h. 2.
3
tsi‟i (Sriwijaya), dan dari puteri raja yang diserahi kekuasaan untuk mengawasi
urusan negara San-Fo-tsi‟i. Mereka mengirimkan perhiasan, rumbia, kamfer, dan
tiga belas potong pakaian.16
Pada saat Sriwijaya tampil dan memerankan kotanya sebagai kota
kosmopolitan sebagai perantara dalam perdagangan Timur jauh dan Timur Tengah,
menurut sumber-sumber Tiongkok, banyak duta Muslim yang dikirim oleh
Sriwijaya ke Kaisar Tiongkok dari abad 10 sampai dengan abad 12 M.17
Hubungan
diplomatik dengan Kekaisaran Tiongkok tidak hanya dilakukan Sriwijaya, tetapi
juga Kerajaan Borneo. Kerajaan di Borneo Barat mengirim beberapa utusannya
yang salah satunya bernama P‟u A-Lu–Hsieh (Abu Abdullah) ke istana Sung. Duta
ini sebenarnya adalah seorang pedagang Arab yang kapalnya sedang berlabuh di
muara sungai Kerajaan Borneo Barat, dan diminta oleh penguasa setempat untuk
memimpin delegasi duta-dutanya ke istana Sung di Tiongkok.18
Hubungan erat yang terjalin antara etnis Tionghoa dan Nusantara disebabkan
oleh faktor perdagangan internasional.19
Hubungan itu didorong oleh
berkembangnya tiga kerajaan besar sejak abad ke-7 M. yakni Dinasti Tang di
Tiongkok, Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani Umayyah di Asia Barat (Timur
Tengah).20
Etnis Tionghoa membawa berbagai jenis barang dagangan seperti
porselen, kapur barus, sutera, produk pabrik (kain, satin, brocade, dan pakaian
berbahan katun dan sebagainya). Transaksi jual beli terjadi di sepanjang pantai utara
Jawa yang dikenal sebagai bandar perdagangan.21
Pasca runtuhnya Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, arus perniagaan etnis
Tionghoa bergeser ke Jawa Timur tepatnya di Keling (Ho-Ling) pada abad ke-7,
dan berkembang pesat pada masa Kerajaan Panjalu (Daha atau Kediri). Sebelumnya
Raja Darmawangsa (991-1007) sudah meletakkan dasar-dasar dan membuka
hubungan diplomatik serta hubungan dagang dengan etnis Tionghoa.22
Hubungan
16
J. Leijten, “Mauro Jambi, the Capital of Srivijaya: According to the writings of I-
Tsing, Chau Ju-kua and Resent”. Studies and Archaeological Findings, 2017, h. 1-44. 17
S. Al Qurtuby, Arus Cina-Islam-Jawa: Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa
dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV&XVI, (Yogyakarta: Inspeal
Ahimsya Karya Press, 2003), h. 75. 18
W. P. Groeneveldt, Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from
Chinese Sources, (Jakarta: Bhratara, 1960), h. 108-110. 19
M. Stuart-Fox, “Southeast Asia and China: The role of history and culture in shaping
future relations”. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic
Affairs, vol. 26, no. 1, 2004, h. 116-139. 20
A. Ibrahim, “Islam in Southeast Asia”. Ar Raniry: International Journal of Islamic
Studies, vol. 5, no. 1, 2018, h. 40-52.; S. M. Imamuddin, “Arab Mariners and Islam in China
(Under the Tang Dynasty 618-906 AC)”. Journal of the Pakistan Historical Society, vol. 32,
no. 3, 1984, h. 155.; Y. Chang, “The Ming Empire: Patron of Islam in China and Southeast-
West Asia”. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, vol. 61, no. 2,
1988, h. 1-44. 21
Uka Tjandrasasmita, Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota Muslim di
Indoneisa, (Kudus: Menara Kudus, 2000), h. 142-144. 22
Tamar Djaja, Pusaka Indonesia: Riwayat Hidup Orang-orang Besar di Tanah Air,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1965), h. 21.
4
dagang antara Tionghoa dan Panjalu di abad 12 berkembang cukup pesat, dan terus
berlanjut sampai masa kepemimpinan Ken Arok yang bergelar Raja Rajasa (1222
M).23
Hubungan antara Nusantara dan Tiongkok juga terjadi pada masa Kaisar
Mongol Kubilai Khan. Sejak tahun 1280, Jawa menjadi salah satu daerah yang
mendapat perhatiannya. Sebagaimana negeri-negeri lain, ke pulau Jawa juga dikirim
utusan pertama untuk menyuruh negeri itu takluk kepadanya dan supaya Raja-raja
Jawa datang ke Tiongkok untuk menyampaikan hormat mereka. Namun,
Kertanegara sebagai Raja Singosari merasa dirinya besar pula dan tidak
memerdulikan desakan tersebut. Lama kelamaan Kertanegara merasa dirinya jemu
dengan desakan Kubilai Khan yang berkali-kali. Akhirnya, Kartanegara menyuruh
untuk membuat cacat muka utusan Tiongkok itu yang bernama Meng Ki. Hal itu
menimbulkan kemarahan Kubilai Khan. Akhirnya Tiongkok mengirim ekspedisi
untuk menghukum Kertanegara dengan pasukan berjumlah 20.000 orang pada tahun
1293. Namun, sesampainya di Jawa, Raja Kertanegara ternyata telah dibunuh oleh
Djayakatwang dari Kediri. Raden Widjaya yang tidak lain adalah menantu
Kertanegara adalah pribadi yang cukup cerdik untuk menjadikan tentara Mongol
sebagai sekutunya. Dengan keadaan ini mereka bersatu untuk menyerang Kediri.
Setelah peperangan yang hebat, Kediri pada akhirnya dapat dikalahkan. Ketika
tentara Mongol hendak pulang ke negerinya, secara tiba-tiba Raden Widjaya beserta
pasukannya menyerang tentara Mongol yang mengakibatkan korban sekitar 3000
tentara Tiongkok.24
Penulis berpendapat bahwa expedisi Mongol tanpa disengaja
telah membantu Raden Wijaya untuk mendirikan Majapahit.
Pada masa Dinasti Ming hubungan antara Nusantara dan Tiongkok kembali
membaik yang sebelumnya sempat terganggu dengan invasi tentara Mongol ke
Jawa. Hal ini dibuktikan dengan diutusnya Cheng Ho untuk memimpin ekspedisi
muhibbah.25
Gaya keramik peninggalan Majapahit yang ditemukan dalam sebuah
penggalian membuktikan pengaruh seni Tionghoa. Menurut catatan tahunan
Melayu, banyak tukang yang berasal dari Tiongkok bekerja di istana Majapahit.26
Hubungan ini menemui puncaknya pada masa Dinasti Ming. Banyak komunitas
Tionghoa yang memegang peran sentral, baik dalam sektor politik maupun
ekonomi, juga di antara mereka ada yang menjadi juru dakwah Islam. Sampai akhir
abad ke-15, tidak kurang dari 43 duta dari Jawa di kirim ke Tiongkok, dan 41 di
antaranya terjadi selama kurang lebih satu abad (1370-1465). Al Qurtuby melihat
hubungan “mesra” itu tidak hanya disebabkan karena faktor ekonomi dan politik,
tetapi hubungan yang dibangun berdasarkan persamaan ideologi.27
Di masa Dinasti Ming (1405-1433), Kaisar Yung-Le memerintahkan Cheng Ho
untuk melakukan kunjungan persahabatan ke negara-negara di Asia Tenggara.
Ekspedisi pertamanya dilakukan pada tahun 1405, ia singgah di bandar Samudera
23
Al Qurtuby, Arus Cina-Islam-Jawa..., h. 76-77. 24
H. J. de Graaf dkk, Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI: Antara Historisitas dan
Mitos, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), h. 146. 25
Tanggok, Menghidupkan Kembali Jalur…, h. 28. 26
De Graaf, Cina Muslim..., h. 146. 27
Al Qurtuby, Arus Cina-Islam-Jawa..., h. 80-81.
5
Pasai dan bertemu dengan Sultan Samudera Pasai bernama Zainal Abidin Bahian
Syah untuk mengadakan hubungan politik dan dagang. Setelah adanya hubungan
baik itu, maka semakin banyak pedagang Tionghoa yang datang ke Samudera Pasai
dan banyak di antara mereka melakukan perkawinan dengan penduduk setempat.28
Menurut prasasti Tain Fei Ling Ying Zhi Ji29
(Catatan tentang Kemujaraban Dewi
Sakti), Cheng Ho melakukan perjalanan muhibbah sebanyak tujuh kali.30
Tjandrasasmita mengatakan sebelum kedatangan Cheng Ho ke Nusantara di abad
ke-15, etnis Tionghoa Muslim sudah aktif di Indonesia. Dalam menjalankan misi
dari Dinasti Ming, perjalanan serta pelayaran yang dilakukannya mempunyai arti
penting bagi rakyat Tiongkok. Ekspedisi pelayaran Cheng Ho membawa 63 unit
kapal dengan awak kapal berjumlah sekitar 27.000. Pengaruh yang dihasilkan dari
pelayarannya tidak hanya dirasakan rakyat Tiongkok saja, namun juga umat Islam
Nusantara, termasuk Indonesia sekarang ini.31
Kesuksesan besar dari pencapaian Cheng Ho dalam misi pelayarannya di
samping faktor kekuatan militer, juga karena didukung identitasnya sebagai seorang
Muslim. Identitas keislaman mampu menjadi perekat sosial dan menciptakan
solidaritas emosional dalam wilayah “jaringan Muslim” di pesisir Samudra Hindia
ketika itu. Bersamaan dengan misi pelayaran, agama Islam sudah menguasai hampir
di setiap pos strategis perdagangan.32
Ma Huan dalam Ying-yai Seng-Lan, ketika
mendarat di Jawa, mendapati etnis Tionghoa Muslim. Mereka melakukan salat dan
berpuasa pada bulan Ramadhan.33
Di sisi lain, kehadiran Cheng Ho mendorong
semangat keislaman penduduk lokal, khususnya daerah yang baru berkenalan
dengan Islam. Kehadiran armada Cheng Ho selalu disambut dengan antusias oleh
penduduk setempat dan pemuka agamanya, sebagaimana yang ditunjukkan Maulana
Malik Ibrahim (w. 1419), salah seorang wali yang tinggal di Gresik, menerima
rombongan Cheng Ho dan Ma Huan. Cheng Ho juga tidak memaksa pengikutnya
yang ingin tinggal menetap di Jawa untuk bergabung dan membaur dengan
komunitas Islam lainnya guna menyebarkan Islam. Hampir setiap wilayah pesisir
yang disinggahinya, Cheng Ho selalu menempatkan etnis Tionghoa Muslim di
daerah-daerah seperti di Sunda Kelapa, Cirebon, Semarang, Demak, Jepara, Tuban,
Gresik dan Surabaya.34
Kedatangan Cheng Ho ke berbagai daerah di Nusantara memberikan kemajuan
dalam berbagai bidang seperti bercocok tanam, alat bajak dari besi, beternak,
28
Mulyana, Runtuhnya Kerajaan Hindu..., h. 83-84 29
Prasasti ini dibangun oleh Cheng Ho di Changle Provinsi Fujian (Hokkian). 30
Kong Yuanzhi, Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah di
Nusantara, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2007), h. 60-61. 31
Uka Tjandrasasmita, “Laksamana Cheng Ho dan Penyebaran Islam di Asia Pasifik”,
Seminar Internasional Fakultas Dakwah IAIN Jakarta, 28 Agustus 1993. 32
Al Qurtuby, Arus Cina-Islam-Jawa..., h. 89. 33
Ma Huan, Ying-yai Sheng-Ian: The Overall Survey of the Ocean's Shores (1433).
Translated by J. V. G. Mills. Edited by Feng Ch‟eng Chun, (Cambridge: The University
Press for the Hakluyt Society, 1970), h. 93.; Lihat juga Claudine Salmon, “The Chinese
Community of Surabaya, from Its Origins to the 1930s Crisis”. Chinese Southern Diaspora
Studies, vol. 3, 2009, h. 23. 34
Al Qurtuby, Arus Cina-Islam-Jawa..., h. 91
6
perdagangan seni ukir, seni bangunan (arsitektur) dan seni budaya lainnnya.
Bahkan, bangsa Indonesia hingga saat ini masih memanfaatkan produk dari hasil
pengetahuan etnis Tionghoa seperti tahu, tauco, mie, bihun, kwetiaw, kecap,
bakpao, bakso, bakpia, capcay, kain sutra, keramik, porselen, kembang api, mercon,
dan sebagainya. Sementara itu, dari Nusantara Cheng Ho membawa tanaman kayu
manis, lada, cengkeh, dan sebagainya.35
Dalam konteks kedatangan awal etnis
Tionghoa di Nusantara menurut Hidayat pada umumnya mereka hanya terdiri dari
laki-laki saja, dan keadaan ini berlangsung sampai berakhirnya Perang Dunia I.36
Etnis Tionghoa kemudian mengadakan perkawinan dengan perempuan lokal,
baik dengan perempuan bangsawan maupun rakyat biasa. Dari perkawinan silang
tersebut muncul istilah “Cina peranakan” sebagai imbangan dari “Cina totok”.37
Di
era pra kolonial, tradisi ini dikenal dengan “kawin silang” antara Tionghoa-Jawa.
Bahkan, banyak orang Jawa yang bangga menyatakan dirinya sebagai keturunan
Tionghoa. Raynal dalam Histoire Philosophique et Politique sebagaimana dikutip
Lombard menulis penduduk pulau Jawa menganggap dirinya keturunan Tionghoa,
meskipun agama dan adat istiadatnya tidak lagi sama.38
Sementara Pires memberi
kesaksian tentang keharmonisan etnis pribumi dan Tionghoa, bahkan Pires melihat
ada penguasa Tionghoa yang memberikan anak perempuannya kepada vasal39
Jawa
untuk dinikahi.40
Pasca kedatangan Belanda ke Indonesia, tradisi ini lambat laun lenyap. Belanda
memisahkan pribumi Jawa dan Tionghoa yang dianggap sebagai “orang asing dari
Timur”. Pemisahan ini terjadi setelah etnis Tionghoa dianggap oleh Belanda sebagai
pesaing utama dalam bidang perdagangan. Puncaknya terjadi pada Oktober 1740
ketika Belanda melakukan pembantaian massal yang dikenal dengan chinezenmoord
(pembantaian etnis Tionghoa), dimana ribuan orang dibunuh dan ratusan rumah
dibakar.41
Pada saat etnis Tionghoa yang ada di Jawa mengalami pembantaian massal
oleh Belanda, Kekaisaran Tiongkok saat itu sudah beralih ke Dinasti Manchu tidak
memerdulikan nasib etnis Tionghoa, bahkan mereka menganggap etnis Tionghoa
rantau tidak ada hubungannya dengan etnis Tionghoa daratan. Bangsa Manchu
sangat antipati terhadap Islam, bahkan mereka khawatir melihat perkembangan
35
Yuanzhi, Muslim Tionghoa…, h. 20-21. 36
Z. M. Hidayat, Masyarakat dan Kebudayaan Cina di Indonesia, (Bandung: Tarsito,
1984), h. 75. 37
Liem Tian Joe, Riwayat Semarang 1416-1931, (Semarang: 1933), h. 12. 38
Dennys Lombard, Nusa Jawa Silang Budaya: Jaringan Asia, (Jakarta: 1996), h. 46-
47. 39
Vasal adalah seseorang yang menjalin hubungan dengan monarki yang
berkuasabiasanya dalam bentuk dukungan militer, perlindungan bersama (mutual
protection), atau pemberian upeti, dan menerima jaminan jaminan serta imbalan tertentu
sebagai gantinya. Sistem ini telah ada sebelum hingga berakhirnya feodalisme di Eropa pada
abad pertengahan. Selain di Eropa, sistem ini juga ditemukan pada kekaisaran Mongolia,
Jepang (Gokenin), dan lainnya. 40
Tome Pires, Suma Oriental, edited & translated by Armando Cortesso, (London:
1944), h. 179. 41
Wiryomartono, “Urbanism and Ethnic…, h. 105-127.
7
Tionghoa Muslim perantauan di Asia Tenggara, yang dianggap bisa mengancam
eksisitensi Konfusianisme dan Taoisme sebagai agama leluhur mereka. Untuk itu
mereka menarik secara besar-besaran Jung-jung yang ada di Asia Tenggara sampai
ke Asia Timur dan pantai barat India untuk dibakar.42
Karena merasa punya
kesamaan “visi dan misi”, Belanda mengadakan koalisi dengan pemerintah
Tiongkok untuk mendatangkan etnis Tionghoa yang berhaluan Konfusius (non
Islam) untuk dipekerjakan di sektor pertanian (Jawa), perkebunan (di Kalimantan),
pertambangan (di Sumatera) dan lain-lain. Pengiriman gelombang imigran dari
Tiongkok itu di samping menguntungkan Belanda secara ekonomi juga sejalan
dengan keinginan pemerintah Tiongkok untuk memutus historisitas Tionghoa
Muslim di Jawa khususnya.43
Itulah sebabnya kenapa di Jawa atau di Indoneisa
pada umumnya yang tampak adalah Konfusianisme ketimbang Islamnya.
Imigran Tionghoa yang datang ke Nusantara sudah pula membawa isteri dan
anak-anaknya, mereka kebanyakan berasal dari suku Hokkian, Hakka dan Canton.
Sampai pertengahan abad ke-19, suku Hokkian merupakan dominant group,
menyebar ke seluruh wilayah Nusantara untuk bertani dan berdagang, serta sebagai
tukang, buruh perkebunan dan pertambangan.44
Pada masa kolonial Belanda memerintah, mereka membuat kebijakan yang
sangat rasialis dengan membagi masyarakat menjadi tiga kelas. Orang Eropa
diposisikan sebagai warga kelas satu, etnis Tionghoa termasuk dalam warga Timur
Asing atau warga kelas dua, dan penduduk asli (pribumi) diposisikan sebagai kelas
yang paling akhir. Nugrahanto mengatakan Belanda juga menciptakan kawasan
pecinan untuk etnis Tionghoa. Mereka hanya boleh tinggal di daerah pecinan dan
tidak boleh tinggal berbaur dengan masyarakat pribumi.45
42
A. Wahid, Mengurai Hubungan Agama dan Negara, (Jakarta: Grasindo, 1999), h.
110. 43
C. I. Ratnapuri, “Chinese Ethnic Perspective on the Confucius Values of Leadership
in West Java Fuqing Organization”. Pertanika Journal of Social Sciences &
Humanities, vol. 28, 2020.; R. Theo & M. W. Leung, “China‟s Confucius Institute in
Indonesia: Mobility, Frictions and Local Surprises”. Sustainability, vol. 10, no. 2, 2018, h.
530.; E. Sutrisno, “Confucius is Our Prophet: The Discourse of Prophecy and Religious
Agency in Indonesian Confucianism”. Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast
Asia, vol. 32, no. 3, 2017, h. 669-718. 44
V. Purcel, The Chinese in Southeast Asia, (Kuala Lumpur: Oxford University Press,
1962), h. i.; K. Ismail, “Imperialism, Colonialism and their Contribution to the Formation of
Malay and Chinese Ethnicity: An Historical Analysis”. Intellectual Discourse, vol. 28, no. 1,
2020, h. 171-193.; J. Stenberg, “From the (Tang) General to the (Jakarta) Specific: Xue
Rengui across Time and Space”. Asian Studies Review, 2020, h. 1-19.; H. Y. Kuo, “South
Seas Chinese in Colonial”. Framing Asian Studies: Geopolitics and Institutions, 2018, h.
231. 45
Widyo Nugrahanto, Bertahan di Perantauan: Wacana Cina Muslim di Nusantara
Abad ke 15 dan ke 16, (Bandung: Uvula Press, 2007), h. 166-167.; Lihat juga S. Sudjarwo,
& P. Pujiati, “The Shifting Tradition of Ethnic Chinese Weddings at Pecinan Village Bandar
Lampung City”. Research on Humanities and Social Sciences, vol. 8, no. 12, 2018, h. 58-
65.; D. Rizaldi, “Ethnic Chinese Social Assimilation in Cibadak Chinatown
Bandung”. International Journal Pedagogy of Social Studies, vol. 3, no. 2, 2018, h. 133-141.
8
Penulis melihat sebagaimana Nugrahanto di atas bahwa kebijakan pemerintah
Belanda dengan membentuk kawasan pecinan dimaksudkan supaya Belanda lebih
mudah mengawasi gerak-gerik mereka, juga agar hubungan baik antara etnis
Tionghoa dan rakyat pribumi menjadi retak. Sebab, Belanda khawatir jika etnis
Tionghoa bersatu dengan pribumi akan menjadi sebuah kekuatan baru yang bisa
mengancam eksistensi mereka.
Dengan tinggalnya etnis Tionghoa di kawasan pecinan membuat mereka
merasa berbeda dengan pribumi. Begitupun etnis pribumi merasa berbeda dengan
etnis Tionghoa. Pada akhirnya, perasaan berbeda itu tidak menciptakan perasaan
kebersamaan, yakni tidak ada lagi sense of belonging dan sense of care di antara
mereka. Keadaan ini membuat pemerintah Belanda dengan mudah menguasai
dengan memanfaatkan kondisi yang ada. Politik Devide et Impera46
yang diciptakan
Belanda berhasil memecah belah hubungan antara etnis pribumi dan Tionghoa.
Sejak saat itu, sikap diskriminatif terhadap etnis Tionghoa terjadi, bahkan sebagian
masih terjadi hingga kini.47
Dengan kebijakan politik sebagaimana disebutkan, etnis
Tionghoa di Indonesia bersama-sama dengan orang Arab dan India digolongkan
sebagai golongan timur asing.
Pada masa kemerdekaan, golongan timur asing dianggap sebagai warga negara
Indonesia apabila mau mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan setia pada
negara Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945, Bab X, Pasal 26, Ayat 1.
Namun, pada pelaksanaannya ada perlakuan yang berbeda bagi etnis Arab, karena
agamanya sama dengan yang dipeluk mayoritas masyarakat Indonesia, maka
mereka dianggap “pri” (pribumi) atau bahkan “asli”, sedangkan etnis Tionghoa,
karena agamanya adalah Tri Dharma (Sam Kao), Budhis dan Nasrani, termasuk
juga etnis India yang beragama Hindu dan Belanda yang beragama Nasrani,
dianggap “non pri”. Dengan stigma “non pri”, kedudukan mereka yang bukan
pribumi, terutama keturunan Tionghoa terasa sekali pendiskriminasiannya. Bahkan,
pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan presiden yang
menekan, bahkan dengan politik pembauran yang bersifat asimilasi paksa, sehingga
sebagai etnis mereka tidak boleh mengekspresikan budayanya. Beberapa peraturan
tersebut dapat dilihat dalam beberapa Keputusan Pemerintah Indonesia, seperti
Pelarangan Sekolah dan Penerbitan Surat Kabar Berbahasa Cina; keputusan
Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tentang Penggantian Nama; Instruksi
Presiden No. 14/1967, yang mengatur Agama dan Kepercayaan serta Adat Istiadat
Keturunan Cina; Keputusan Presiden No. 240/1967 tentang Kebijakan Pokok
46
K. Saddhono & S. Supeni, “The Role of Dutch Colonialism in the Political Life of
Mataram Dynasty: A Case Study of the Manuscript of Babad Tanah Jawi”. Asian Social
Science, vol. 10, no. 15, 2014, h. 1-7. 47
S. Lubis & R. Buana, “Stereotypes and Prejudices in Communication between
Chinese Ethnic and Indigenous Moslem in Medan City, North Sumatra Province–
Indonesia”. Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal, vol.
2, no. 2, 2020, h. 513-522.; S. Turner & P. Allen, “Chinese Indonesians in a rapidly
changing nation: Pressures of ethnicity and identity”. Asia pacific viewpoint, vol. 48, no. 1,
2007, h. 112-127.; C. Y. Hoon, “Assimilation, multiculturalism, hybridity: The dilemmas of
the ethnic Chinese in post-Suharto Indonesia”. Asian Ethnicity, vol. 7, no. 2, 2006, h. 149-
166.
9
menyangkut WNI Keturunan Asing; dan Instruksi Presidium Kabinet No.
37/U/IN/6/1967 tentang Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina.48
Kategorisasi pribumi dan non pribumi yang direproduksi selama masa Orde
Baru membuat etnis Tionghoa semakin mengeksklusifkan diri. Akan tetapi,
serangkaian usaha pembatasan ini juga diiringi dengan langkah pemerintah yang
mendukung komunitas etnis Tionghoa untuk melakukan ekspansi bisnis dalam
segala sektor. Komunitas etnis Tionghoa di Indonesia lebih mengedepankan
hubungan kekerabatan inter-etnis daripada membangun relasi dengan masyarakat
lokal tempat mereka bermukim. Dalam sudut pandang sebagian masyarakat lokal,
kecenderungan etnis Tionghoa untuk mengeksklusifkan diri memperuncing
segregasi, karena mayoritas etnis Tionghoa dominan dalam sektor ekonomi.49
Kebijakan asimilasi50
secara menyeluruh diterapkan selama pemerintahan Orde
Baru (1966-1998). Pemerintah menegaskan bahwa warga negara Indonesia
keturunan Tionghoa harus segera berintegrasi dan berasimilasi dengan masyarakat
Indonesia asli.51
Namun, dalam praktik seringkali asimilasi berjalan dengan kabur
dan bertentangan, bahkan beberapa kebijakan Orde Baru cenderung anti-asimilasi
karena pertimbangan kondisi politis. Sebagai contoh, toleransi terhadap agama-
agama minoritas dan pembedaan antara pribumi dan non pribumi cenderung
malahan memilah, dan bukan mempersatukan etnis Tionghoa dan orang Indonesia
48
A. Dawis, “Chinese Education in Indonesia: Developments in the Post-1998
Era”. Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia, 2008, h. 75-96.; L. Suryadinata,
“Indonesian State Policy Towards Ethnic Chinese: From Assimilation to
Multiculturalism”. Chinese Indonesians: State Policy, Monoculture and Multiculture, 2004,
h. 1-16.; A. Freedman, “Political Institutions and Ethnic Chinese Identity in
Indonesia”. Asian Ethnicity, vol. 4, no. 3, 2003, h. 439-452. 49
D. Susilo, “Chinese Cultural Values and its Influence on Chinese Indonesian
Entrepreneurial Culture”. Asian People Journal (APJ), vol. 3, no. 1, 2020, h. 201-208.; M.
Z. Tadjoeddin, “Inequality and Exclusion in Indonesia”. Journal of Southeast Asian
Economies, vol. 36, no. 3, 2019, h. 284-303.; H. Liu & Y. Zhou, “New Chinese Capitalism
and the ASEAN Economic Community”. In The sociology of Chinese capitalism in
Southeast Asia, (Palgrave Macmillan, Singapore, 2019), h. 55-73. 50
Asimilasi adalah proses perubahan kebudayaan secara total akibat membaurnya dua
kebudayaan yang asli, atau kebudayaan yang lama tidak nampak lagi. Koentjaraningrat
mendefinisikan pembauran sebagai suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan
manusia dengan latar kebudayaannya yang berbeda. Setelah mereka bergaul secara intensif,
sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan masing-masing berubah menjadi unsur kebudayaan
campuran. Lihat D. Parisi, F. Cecconi, & F. Natale, “Cultural Change in Spatial
Environments: the Role of cultural assimilation and internal changes in cultures. Journal of
Conflict Resolution, vol. 47, no. 2, 2003, h. 163-179.; M. C. Dato-on, “Cultural Assimilation
and Consumption Behaviors: A Methodological Investigation”. Journal of Managerial
Issues, 2000, h. 427-445.; J. M. Yinger, “Toward a Theory of Assimilation and
Dissimilation”. Ethnic and Racial Studies, vol. 4, no. 3, 1981, h. 249-264. 51
G. Dwipayana dan R. K. Hadimadja, Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya,
(Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1989), h. 279.
10
asli.52
Artinya, etnis Tionghoa tetap terpisah dari komunitas tuan rumah
(Indonesia).53
Jadi, menurut penulis dalam prakteknya tidak terjadi pembauran.
Kebijakan asimilasi yang digaungkan pemerintah Orde Baru menurut beberapa
pengamat gagal karena tidak diikuti dengan produk-produk hukum yang
mendukung terjadi pembauran, sehingga kebijakan asimilasi tidak membuahkan
hasil yang yang maksimal. Sama hal juga dengan program yang dijalankan mantan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mencoba mengindonesiakan etnis
Tionghoa adalah bukan solusi yang tepat. Pembauran menurut Kite harusnya
dipusatkan pada usaha memperbaiki hubungan antar dua kelompok. Pembauran
bukan berarti tanpa perbedaan; pembauran bukan berarti kehilangan kebudayaan,
biarkan pembauran berjalan secara alami.54
Pasca jatuhnya Soeharto yang diawali oleh demonstrasi massif dari mahasiswa
dan kerusuhan anti- Tionghoa pada Mei 1998 membuat konsep asimilasi pemerintah
Indonesia mengalami perubahan secara bertahap, yang puncaknya terjadi pada masa
Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Gus Dur55
menetapkan konsep bangsa Indonesia
yang non-rasial. Lebih lanjut Ia mengatakan Indonesia terdiri dari berbagai etnik
yang membentuk kebangsaan kita. Salah satu etnik tersebut adalah etnis Tionghoa
sebagai bagian terpadu dari bangsa Indonesia. Ia mengakui etnis Tionghoa dalam
aspek budaya termasuk agama dan kepercayaan mereka, juga tidak melihat
kontradiksi antara etnisitas Tionghoa dan konsep bangsa Indonesia. Meskipun
demikian, ia menekankan arti pentingnya kesetiaan politik dan penerimaan atas
nasionalisme Indonesia yang harus dimiliki oleh mereka.56
Dengan kata lain, konsep
ini memberi pengakuan keberadaan budaya etnis sebagai bagian dari budaya
Indonesia dengan memberikan kebebasan kepada masing-masing etnis untuk
mengekspresikan budayanya.
52
L. Suryadinata, “Chinese Indonesians in Post-Suharto Indonesia: Democratisation
and Ethnic Minorities by Chong Wu-Ling”. Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast
Asia, vol. 35, no. 1, 2020, h. 165-168.; H. Kurniawan, “Ethnic Chinese during the New
Order: Teaching Materials Development for History Learning based on
Multiculturalism”. Paramita: Historical Studies Journal, vol. 30, no. 1, 2020, h. 46-54.; W.
Wasino, S. Putro, A. Aji, E. Kurniawan & F. A. Shintasiwi, “From Assimilation to Pluralism
and Multiculturalism Policy: State Policy Towards Ethnic Chinese in Indonesia”. Paramita:
Historical Studies Journal, vol. 29, no. 2, 2019, h. 213-223. 53
D. F. Anwar, “Indonesia-China Relations: Coming Full Circle?. Southeast Asian
Affairs, no. 1, 2019, h. 145-161. 54
E. Kite, “Chinese Cultural Identity: Suharto's Wisdom and its Success in Achieving
Complete Integration”. In ACICIS Field Report, (Malang: Muhammadiyah University,
2004), h. 1-39. 55
Ketika A. Wahid (Gus Dur) menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ia
mencabut Peraturan No.14/1967 yang membatasi praktik adat istiadat dan agama etnis
Tionghoa pada tingkat pribadi. Ia juga merayakan Tahun Baru etnis Tionghoa secara terbuka
dengan etnis Tionghoa yang disponsori oleh perhimpunan keagamaan Konghucu Indonesia
(Matakin). 56
A. Wahid, “Beri Jalan Orang Cina”, dalam J. Jahja (peny.), Nonpri di Mata Pribumi,
(Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1991). h. 224–228.
11
Secara legal formal konsep di atas direalisasikan dengan dikeluarkannya
Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 pada 17 Januari 2000. Gus Dur
mengeluarkan kebijakan revitalisasi adat istiadat dan kepercayaan Tionghoa
sekaligus mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967. Kebijakan ini selanjutnya didukung
oleh Presiden Megawati dengan ditetapkannya Imlek sebagai hari nasional.57
Pergeseran iklim politik tersebut mendorong etnis Tionghoa untuk berpartisipasi
dalam masyarakat Indonesia. Pembauran etnis Tionghoa bisa dilihat dalam
keterlibatan mereka dalam berbagai sektor kehidupan. Persatuan Islam Tionghoa
Indonesia (PITI) sebagai organisasi di internal Tionghoa Muslim melakukan upaya
konsolidasi untuk beradaptasi sekaligus eksistensi. Tionghoa Muslim berbaur
dengan masyarakat dan aktif di berbagai organisasi serta tidak menonjolkan sebagai
etnis Tionghoa.58
PITI menggunakan strategi pendekatan kebudayaan agar efektif dalam
berdakwah, mereka tetap mempertahankan identitas etnis Tionghoa dan beradaptasi
dengan budaya setempat.59
Sunano mengatakan pola dakwah dengan merayakan
Tahun Baru etnis Tionghoa dalam bentuk pengajian Imlek perlu dikembangkan
dengan mengkaji berbagai tradisi kebudayaan Tionghoa yang tidak menjadi bagian
dari ritual agama.60
Dengan melakukan demistifikasi kebudayaan Tionghoa dan
diadopsi menjadi bagian kebudayaan Islam, akan memberikan pengaruh yang
berbeda dalam pola dakwah Islam sekarang yang makin kering budaya dan hanya
berkutat pada doktrin.
Konsep sebagaimana di atas juga direalisasikan di Cirebon karena mereka
memiliki hubungan erat dalam aspek sejarah. Menurut naskah Purwaka Tjaruban
Nagari61
etnis Tionghoa sudah ada di Cirebon jauh sebelum Kesultanan Cirebon
berdiri. Hubungan Keraton Cirebon dengan etnis Tionghoa sudah terjalin lama yang
ditandai dengan keberadaan etnis Tionghoa sejak tahun 1415 M. Peristiwa
monumental itu terjadi pada saat pasukan dari Tiongkok yang dinahkodai Cheng Ho
mendarat di pelabuhan Cirebon dengan membawa pasukan lebih dari 23.000 dengan
57
E. Kuntjara, & C. Y. Hoon, “Reassessing Chinese Indonesian stereotypes: two
decades after Reformasi”. South East Asia Research, 2020, h. 1-18.; S. Suprajitno,
“Reconstructing Chineseness: Chinese Media and Chinese Identity in Post-Reform
Indonesia”. Kemanusiaan: The Asian Journal of Humanities, vol. 27, no. 1, 2020.; Z.
Alkatiri, A. L. Waworuntu, F. Gani & R, De Archellie, “Medan Chinese and Their Stigma:
Grabbing Power in Multicultural Society. International Review of Humanities Studies, vol.
4, no. 1, 2019. 58
E. Purwati & E. F. Rusydiyah, “Transformative Islamic Education of Convert
Chinese Muslim”. Journal of Talent Development and Excellence, vol. 12, no. 1, 2020, h.
164-178. 59
A. Rohman, “Chinese–Indonesian Cultural and Religious Diplomacy”. Journal of
Integrative International Relations, vol. 4, no. 1, 2019, h. 1-24. 60
Sunano, Muslim Tionghoa di Yogyakarta, (Yogyakarta: Penerbit Mata Bangsa, 2017),
h. 325. 61
Atja, Carita Purwaka Caruban Nagari: Karya Sastra sebagai Sumber Pengetahuan
Sejarah, (Bandung: Proyek Pemuseuman Jawa Barat, 1986), h. 31.; Lihat juga B. S. Budi,
“Tjarita Purwaka Tjaruban Nagari (Sedjarah Muladjadi Tjirebon) 1972”. Journal of Asian
Architecture and Building Engineering, no. 4, 2005, h.1-8.
12
63 perahu. Filolog Cirebon, Raden Ahmad Rafan Safari Hasyim menjelaskan,
Cheng Ho menginap di Cirebon selama tujuh hari. Dalam waktu singkat tersebut
pasukan Cheng Ho ada yang melakukan perkawinan dengan penduduk Cirebon.
Jadi, hubungan antara Cirebon dan Tiongkok sangat erat dan sudah terjadi jauh
sebelum ada Kerajaan Cirebon.62
Menurut laporan Ma Huan sebagaimana dalam bukunya Ying Yai Sheng Lan,
Cirebon tertulis dengan nama Che Li Wen.63
Che Li Wen adalah salah satu daerah
yang pernah dikunjungi Cheng Ho beserta pasukannya pada tahun 1415. Kunjungan
ini juga terdapat dalam kitab Purwaka Caruban Nagari yang menyebut istilah
Cirebon berasal dari kata “Caruban”, kemudian “Carbon” dan akhirnya Cirebon.
Caruban berarti campuran, karena tempat itu dahulunya didiami oleh penduduk dari
berbagai bangsa, agama, bahasa dan tulisan mereka menurut bawaannya masing-
masing serta pekerjaan mereka berlainan. Sementara kata “Carbon” menurut para
wali disebut “Puser Jagad” karena Cirebon terletak di tengah-tengah pulau Jawa.
Penduduk setempat menyebut Cirebon dengan sebutan Nagari Gede, lama
kelamaan diucapkan oleh orang kebanyakan menjadi “Garage”, dan selanjutnya
menjadi “Grage”. Menurut penduduk setempat “Grage” berasal dari Glagi yaitu
nama udang kering untuk bahan membuat terasi. Secara bahasa, Cirebon berasal
dari Ci-rebon. “Ci” dalam bahasa Sunda artinya air, sedangkan “rebon” adalah
sejenis udang kecil yang merupakan bahan untuk membuat terasi.64
Berdasarkan peta dunia yang dibuat Diego Ribeiro tahun 1529, Cirebon ketika
itu disebut dengan nama Tjurban. Sementara perjalanan orang-orang Belanda
pertama kali mendarat di Banten tahun 1596. Diberitakan bahwa kota Charabaon
(Cirebon) itu indah dan besar, diperkokoh dengan tembok yang kuat dan terdapat
sungai yang mengandung air tawar. De Haan mengatakan tembok yang
mengelilingi Keraton Cirebon dibuat sekitar tahun 1590 atas prakarsa Senopati
Mataram sebagai tanda perekrutan dengan Panembahan Ratu.65
Lain halnya Pires
yang pernah berkunjung ke Cirebon, dimana ia bercerita tentang kondisi pelabuhan
Cirebon, barang komoditi yang diperjualbelikan serta jumlah penduduk yang ada.
Dari catatan Pires dapat diketahui pada masa itu Cirebon memiliki pelabuhan yang
bagus dan ramai. Banyak kapal yang berlabuh di sana antara lain 3 atau 4 junk dan
beberapa lancara. Mengenai kapal, Pires hanya mencatat junk dan lancara, sebab
pada masa itu berlaku tradisi menilai sebuah pelabuhan dari kemampuannya
dilabuhi kapal besar yaitu junk dan lancara. Meskipun perahu-perahu kecil tidak
tercatat dalam tulisan Pires, namun keberadaannya dipastikan lebih banyak.
Keramaian pelabuhan Cirebon juga dapat dilihat dari jumlah penduduknya yang
sudah mencapai seribu jiwa dengan lima atau enam saudagar, salah satunya Pate
62
“Sejarah Warga Tionghoa di Cirebon”, dalam Radar Cirebon, 29 Januari 2017.
http://www.radarcirebon.com/tag/sejarah-warga-tionghoa, (Diakses, 23 Januari, 2019). 63
Ma Huan, Ying-yai Sheng-Ian:…, h. 23. 64
Atja, Tjarita Purwaka Tjaruban Nagari, (Jakarta: Ikatan Karyawan Museum, 1972),
h. 31.; Lihat juga A. Sobana Hardjasaputra dan Tawalimuddin Haris (ed.), Cirebon dalam
Lima Zaman Abad ke-15 hingga Pertengahan Abad ke-20, (Bandung: Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2011), h.19-20. 65
F. de Haan, Oud Batavia, (Bandung: 1935), h. 38.
13
Quedir seorang saudagar yang cerdik, berani dan dihormati.66
Dari catatan ini juga
dapat diketahui bahwa salah satu barang komoditi Cirebon adalah beras.
Hubungan antara etnis Tionghoa dengan pihak keraton telah terjadi sejak
Syarif Hidayatullah (1479-1568).67
Hubungan di antara mereka menjadi semakin
akrab dengan dipersuntingnya putri Ong Tien sebagai salah satu istri Sunan Gunung
Djati. Ong Tien adalah putri kaisar dari Dinasti Ming. Konon putri ini jatuh hati
pada Sunan Gunung Jati setelah pandangan pertamanya. Walaupun kaisar tidak
mengijinkan namun putri tetap bersikeras pada keinginannya, hingga kaisar
mengijinkannya. Dengan membawa barang-barang berharga dari istana negeri
Tiongkok seperti guci, piring, pot dan benda-benda keramik lainnya, puteri bertolak
ke Cirebon dengan menggunakan kapal layar Kekaisaran Tiongkok yang dikawal
oleh Panglima Lie Guan Cang dan nakhoda Lie Guan Hian. Setelah sampai di
Cirebon, dilangsungkan pernikahan antara Sunan Gunung Djati dengan putri Ong
Tien. Putri dan para pengawalnya masuk Islam dan beralih nama dengan Ratu Mas
Rara Sumanding.68
Penulis sepakat dengan beberapa pendapat yang mengatakan
bahwa dari puteri Tiongkok inilah perluasan Keraton Cirebon banyak menggunakan
hiasan dinding dari porselen buatan Tiongkok. Tidak sedikit pula hiasan berbentuk
guci dari Dinasti Ming yang dibawa ke Cirebon seperti yang masih tersimpan
sekarang.
Dalam segi pemerintahan, etnis Tionghoa juga memiliki kedudukan yang
cukup penting yaitu dengan diangkatnya seorang berkebangsaan Tiongkok sebagai
Sah Bandar di Cirebon. Sah Bandar ini bertanggung jawab atas pengawasan
kegiatan di pelabuhan dan berperan sebagai penghubung antara pedagang asing
yang akan masuk ke Cirebon dengan Sultan Cirebon. Dalam bidang yang lain, etnis
Tionghoa ini juga dikenal baik dalam hal kemampuannya dalam pembuatan uang
logam. Dalam kepandaian tersebut mereka telah memperoleh kepercayaan yang
tinggi dari para Sultan Cirebon. Hal itu diketahui dari data sejarah yang menyatakan
bahwa setelah wafatnya dua pembesar Cirebon yaitu Reksanegara dan Suradinata
yang bertugas membuat uang logam, para Sultan Cirebon mengontrak etnis
Tionghoa untuk membuat mata uang logam Cirebon.69
Dunia perdagangan di Cirebon ketika itu tidak hanya mengenal uang logam
yang dikeluarkan oleh Kerajaan Cirebon, tetapi juga mengenal uang-uang lain
dalam perdagangan. Uang-uang tersebut antara lain adalah sour dari Perancis, mata
66
Pires, Suma Oriental..., h. 183. Lihat juga P. H. Djajadiningrat, “Kanttekeningen bij,
Het Javaanse rijk Tjerbon in de eerste eeuwen van zijn bestaan”. (Nr. 1487). Bijdragen tot
de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast
Asia, vol. 113, no. 4, 1957, h. 380-392. 67
A. N. Wahyu, Sajarah Wali Syeikh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati: Naskah
Mertasinga, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2005).; A. N. Wahyu, Sajarah Wali Syeikh Syarif
Hidayatullah Sunan Gunung Jati: Naskah Kuningan, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2007). 68
P. S. Sulendraningrat, Sejarah Cirebon, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 21-22. 69
A. Schottenhammer, “China‟s Increasing Integration into the Indian Ocean World
Until Song 宋 Times: Sea Routes, Connections, Trades”. In Early Global Interconnectivity
Across the Indian Ocean World, vol. I, (Cham: Palgrave Macmillan, 2019), h. 21-52.; S.
Suparman, S. Sulasman, & D. Firdaus, “Political Dynamics in Cirebon from the 17th to 19th
Century”. Tawarikh, vol. 9, no. 1, 2017, h. 49-58.
14
uang dari Inggris, Hindia Belanda dan kepeng-kepeng Tiongkok. Di antara mata
uang yang ada, uang picis buatan Cirebon merupakan alat pembayaran yang kurang
bagus dan nilainya turun naik. Untuk itulah pada perkembangan selanjutnya, mata
uang logam Cirebon menggunakan huruf latin dan huruf Tiongkok.70
Pemakaian
huruf latin mungkin lebih disebabkan oleh faktor politik dimana kekuasaan dari
pengaruh Belanda telah begitu kuat dalam pemerintahan Kesultanan Cirebon.
Tentang pemakaian huruf Tiongkok kemungkinan disebabkan oleh karena
pembuatnya adalah etnis Tionghoa yang dikontrak Sultan Cirebon. Selain itu,
keberadaan jenis huruf Tiongkok mungkin juga dilatarbelakangi oleh penguasa,
agar mata uang Cirebon dapat lebih diterima dalam perdagangan saat itu. Pada masa
itu picis-picis Tiongkok memegang peranan penting dalam perdagangan di Jawa,71
hingga mampu menguasai sebagian besar pemakaian uang. Dalam konteks ini, etnis
Tionghoa di Indonesia telah ikut memperkaya dan diperkaya oleh kebudayaan suku-
suku Indonesia lainnya, sehingga terjadi akulturasi yang unik dan amat kaya
manifestasinya pada ragam budaya Indonesia. Penulis melihat akulturasi yang
intens terjadi pada masa pra kolonial terutama pada abad XV dan XVI.
Clyne dan Jupp mendefinisikan akulturasi sebagai sebuah keniscayaan dan
tidak bisa dihindari apalagi dengan meningkatnya pernikahan antar etnis. Menurut
keduanya akulturasi berbeda dengan asimilasi, dimana dalam akulturasi kelompok
atau individu tidak kehilangan identitas asalnya, sedangkan asimilasi berarti
penghapusan karakteristik yang ada pada masing-masing kelompok atau individu.72
Sementara Berry berpendapat akulturasi dalam praktiknya cenderung mendorong
lebih banyak perubahan di salah satu kelompok daripada yang lainnya, sedangkan
asimilasi bersifat reaktif dan kreatif karena merangsang wujud-wujud budaya baru
yang tidak ditemukan dalam salah satu budaya yang terjadi kontak.73
Berry dalam
karyanya yang lain mengatakan asimilasi merupakan salah satu jenis akulturasi.
Artinya, akulturasi juga bisa menimbulkan tumbuhnya budaya baru yang tidak ada
pada kelompok-kelompok tersebut.74
Lebih jauh Berry mengatakan akulturasi tidak
hanya terjadi pada budaya tetapi juga pada psikologis seseorang. Akulturasi
psikologis terjadi sebagai akibat dari adanya individu yang berakulturasi. Dalam
konteks ini faktor budaya mempunyai pengaruh yang signifikan pada
perkembangan dan tampilan perilaku individu.75
Akulturasi psikologis dipengaruhi
banyak faktor, tidak hanya faktor masyarakat asal tetapi juga oleh masyarakat
permukiman baru. Selain itu, adanya kebijakan pemerintah tentang imigrasi,
70
Z. Masduqi, “Penggunaan Dinar-Dirham dan Fulus: Upaya Menggali Tradisi yang
Hilang (Studi Kasus di Wilayah Cirebon)”. Holistik, vol. 13, no. 2, 2012. 71
R. Ptak, “China and the Trade in Cloves, circa 960-1435”. Journal of the American
Oriental Society, 1993, h. 1-13. 72
M. Clyne & J. Jupp (ed.), “Epilogue: A Multicultural Future”. In Multiculturalism
and Integration: A Harmonious Relationship, (ANU Press, 2011), h. 191-198. 73
J. W. Berry, “Acculturation and Adaptation in a New Society”. International
Migration, vol. 30, 1992, h. 69-69. 74
J. W. Berry, “Globalisation and Acculturation”. International Journal of Intercultural
Relations, vol. 32, no. 4, 2008, h. 328-336. 75
J. W. Berry, “Cross‐cultural Psychology: A Symbiosis of Cultural and Comparative
Approaches”. Asian Journal of Social Psychology, vol. 3, no. 3, 2000, h. 197-205.
15
ideologi dan sikap dominan masyarakat pendatang, serta dukungan sosial, dan yang
tidak kalah pentingnya lagi adalah tingkat pribadi seseorang dalam beradaptasi ikut
berkontribusi pada akulturasi psikologis.76
Ilmuwan yang menganggap sama konsep akulturasi dan asimilasi dapat
ditelusuri dalam pendapat Gillin dan Gillin misalnya, memparalelkan dua konsep
tersebut dengan mengatakan asimilasi dan akulturasi dapat terjadi apabila terpenuhi
beberapa hal, di antaranya ada toleransi; kesempatan dalam bidang ekonomi;
penghormatan terhadap orang lain dan kebudayaannya; perkawinan campur; dan
adanya ancaman dari luar.77
Sementara Koentjaraningrat ikut mendefinisikan
akulturasi sebagai sebuah proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia
dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu
kebudayaan asing sehingga unsur-unsur asing itu lambat laun diterima dan diolah ke
dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan
itu. Seperti telah diuraikan sebelumnya, suatu unsur kebudayaan tidak pernah
didifusikan secara terpisah, melainkan senantiasa dalam suatu gabungan atau
kompleks yang terpadu.78
Dari beberapa teori akulturasi di atas, penulis cenderung mengikuti pendapat
Berry dan Koentjaraningrat, serta tidak sependapat dengan teorinya Gillin yang
menganggap sama antara akulturasi dan asimilasi. Menurut penulis dalam akulturasi
masing-masing kelompok tidak kehilangan identitas etnis. Kedua kebudayaan atau
lebih itu bertemu dan membentuk kebudayaan baru tanpa keduanya kehilangan ciri
khas masing-masing. Sementara di dalam asimilasi masing-masing etnis kehilangan
keunikannya, lalu muncul suatu budaya baru yang tidak ada di masing-masing
kelompok atau biasa disebut melting pot.79
Secara umum masyarakat di belahan dunia manapun memiliki unsur-unsur
budaya yang universal berupa bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan
hidup, mata pencaharian, kesenian, dan bahkan agama. Dalam proses akulturasi
budaya ini terjadi perubahan pada masing-masing unsur budaya. Perubahan tersebut
tergantung pada intensitas interaksi sosial yang terjadi pada kedua budaya ini dan
76
J. W. Berry, “Achieving a Global Psychology”. Canadian Psychology, vol. 54, no. 1,
2013, h. 55. 77
Gillin & Gillin, Cultural Sociology: A Revision and of an Introduction to Sociology,
(New York: The Macmillan Company, 1948), h. 529-530. 78
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990). 79
Melting pot (kuali peleburan) adalah metafora untuk masyarakat heterogen yang
semakin homogen. Elemen yang berbeda “melebur menjadi satu” sebagai suatu kesamaan
budaya yang harmonis. Teori melting pot pertama kali menjadi terkenal ketika pada 1782, J.
Hector St. John de Crevecoeur, seorang imigran dari Perancis, menggambarkan homogenitas
demografis Amerika Serikat sebagai terdiri dari “individu dari semua bangsa.... dicampurkan
ke dalam ras manusia baru, yang pekerjaan dan keturunannya suatu hari akan menyebabkan
perubahan besar dalam dunia”. Lihat A. Brons, P. Oosterveer, & S. Wertheim-Heck,
“Feeding the Melting Pot: Inclusive Strategies for the Multi-ethnic City”. Agriculture and
Human Values, 2020, h. 1-14.; M. Berray, “A Critical Literary Review of the Melting Pot
and Salad Bowl Assimilation and Integration Theories”. Journal of Ethnic and Cultural
Studies, vol. 6, no. 1, 2019, h. 142-151.; F. C. Berumen, “Resisting Assimilation to the
Melting Pot”. Journal of Culture and Values in Education, vol. 2, no. 1, 2019, h. 81-95.
16
sikap penerimaan dari masyarakat pendukung kedua budaya tersebut. Begitupun
masyarakat Tionghoa yang berdiam di Cirebon sejak awal telah membawa budaya
dan tradisi dari tanah leluhur, namun kemudian mengalami akulturasi ketika
berinteraksi dengan masyarakat Cirebon.
Tylor (antropolog Inggris) dalam bukunya Primitive Culture (1871)
mengatakan budaya adalah keseluruhan yang kompleks dari cakupan pengetahuan,
kepercayaan, seni, moral, hukum, dan adat istiadat, termasuk kemampuan dan
kebiasaan yang diperoleh setiap orang sebagai anggota masyarakat. Lebih lanjut
Tylor mengatakan bahwa budaya dipelajari sebagai anggota masyarakat. Oleh
karena itu, untuk mempelajari budaya seseorang harus menjadi bagian dari
masyarakat.80
Sementara Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai
keseluruhan sistem gagasan dan tindakan serta hasil karya manusia dalam rangka
menunjang kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan
belajar.81
Senada dengan Koentjaraningrat, Soemardjan dan Soemardi mengatakan
kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat
menghasilkan teknologi dan kebudayaan jasmaniah (material culture) yang
diperlukan manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya
dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.82
Pertemuan arus kebudayaan dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu
yang wajar dan alamiah, serta bernilai positif karena manusia merupakan makhluk
sosial, politis dan ekonomis. Kebudayaan sejatinya merupakan world view83
sekaligus way of life84
dari suatu kelompok masyarakat yang membedakannya
dengan kelompok masyarakat lainnya. Pada dasarnya kebudayaan merupakan
identitas dari suatu masyarakat. Identitas terinternalisasi ke dalam gagasan
keyakinan dan berbahasa, bahkan dalam cara berpakaian dan lainnya yang
kemudian mewujud dalam keragaman etnis dan ras. Mengingat budaya yang
dihasilkan setiap negara itu berbeda dan variatif, maka arus pertemuan budaya kerap
menimbulkan kontestasi dan eskalasi yang melahirkan benturan antara satu
80
E. B. Tylor, Primitive Culture, (New York: Harper Torch Books, 1871). 81
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Yogyakarta: 1981), h.181. 82
Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi, (Jakarta:
Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964), h. 113. 83
C. Hubley, J. Hayes, M. Harvey, & S. Musto, “To the victors go the existential spoils:
The mental-health benefits of cultural worldview defense for people who successfully meet
cultural standards and valued goals”. Journal of Social and Clinical Psychology, vol. 39, no.
4, 2020, h. 276-314.; C. Wei, S. Dai, H. Xu, & H. Wang, “Cultural worldview and cultural
experience in natural tourism sites. Journal of Hospitality and Tourism Management, vol.
43, 2020, h. 241-249. 84
L. Pavlyshyn, O. Voronkova, M. Yakutina, & E. Tesleva, “Ethical Problems
Concernig Dialectic Interaction of Culture and Civilization”. Journal of Social Studies
Education Research, vol. 10, no. 3, 2019, h. 236-248.; J. Parks, “Defending the American
Way of Life: Sport, Culture, and the Cold War ed. by Toby C. Rider”. Journal of Arizona
History, vol. 60, no. 3, 2019, h. 388-390.
17
kebudayaan dengan kebudayaan lain atau antara satu peradaban dengan peradaban
lainnya.85
Indonesia sebagai bangsa yang berakar pada budaya yang beragam, sudah
seharusnya membuat pertemuan arus budaya antara satu sama lain bisa berdampak
positif dan saling memperkaya masing-masing kebudayaan. Namun, dalam
realisasinya, pertemuan antar budaya bisa juga melahirkan ketimpangan dan
benturan jika suatu kelompok mayoritas mendominasi dan memaksakan adanya
pembauran terhadap budaya lain yang notabene kelompok minoritas.86
Bahkan,
lebih jauh pemerintah membuat seperangkat aturan yang menyudutkan kelompok
minoritas. Pemerintah melarang penggunaan simbol-simbol Tionghoa dan dipaksa
untuk melepaskan seluruh identitas yang berbau Tionghoa didepan publik.
Kebijakan ini tidak pelak lagi menimbulkan benturan-benturan dan letupan sosial.87
Kerusuhan sosial antar etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi terjadi sejak
jaman kolonial. Tahun 1740 terjadi kerusuhan besar pertama yang menewaskan
10.000 orang Tionghoa. Kemudian, perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825-
1830. Keadaan ini terus berlanjut di tahun 1965, etnis Tionghoa dianggap terlibat
dalam gerakan komunisme, hingga akhirnya seluruh simbol yang bernuansa
Tionghoa harus dihapuskan.88
Di masa Orde Baru, pemerintah mengambil langkah
yang dianggap penting, salah satunya adalah membersihkan unsur-unsur PKI dalam
segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk Tiongkok sebagai negara
dan peranakannya yang dianggap sebagai pendukung PKI.
Uraian di atas menunjukan bahwa kontak budaya antara etnis Tionghoa dengan
masyarakat pribumi sudah terjalin cukup lama, jauh sebelum Belanda datang ke
Nusantara. Maka wajar jika terjadi kontak yang intens termasuk dalam penyebaran
ajaran Islam. Kontak budaya yang intens itu melahirkan akulturasi antara kedua
kebudayaan baik dalam bentuk fisik seperti arsitektur bangunan, teknologi
85
R. Diprose & M. N. Azca, “Conflict Management in Indonesia‟s Post-authoritarian
Democracy: Resource Contestation, Power Dynamics and Brokerage”. Conflict, Security &
Development, vol. 20, no. 1, 2020, h. 191-221.; G. Gürpinar, “Foreign Policy as a Contested
Front of the Cultural Wars in Turkey”. Uluslararası İlişkiler/International Relations, vol.
17, no. 65, 2020, h. 3-21.; J. Abbink, “Religion and Violence in the Horn of Africa:
Trajectories of Mimetic Rivalry and Escalation between „Political Islam‟and the
State”. Politics, Religion & Ideology, 2020, h. 1-22. 86
J. Lee, “Promoting Majority Culture and Excluding External Ethnic Influences:
China‟s Strategy for the UNESCO „intangible‟cultural heritage list. Social Identities, vol.
26, no. 1, 2020, h. 61-76.; R. Antony, “Emerging Ethnic Minority Sub-cultures: young
Tamils in the Post-war Context in the Tamil-dominated Areas in Sri Lanka”. Ethnic and
Racial Studies, vol. 43, no. 10, 2020, h. 1909-1928.; R. Evans, “Interpreting family struggles
in West Africa across Majority-Minority world Boundaries: Tensions and
Possibilities”. Gender, Place & Culture, vol. 27, no. 5, 2020, h. 717-732. 87
L. Suryadinata, Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia, (Jakarta: Kompas,
2010), h. 193-210. 88
Onghokham, Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Cina: Sejarah Etnis Cina Indonesia,
(Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), h. 19.
18
perkapalan, pertanian dan perdagangan.89
Adapun non fisiknya seperti dalam
berbahasa dan pola berperilaku antara dua bangsa tersebut. Penulis melihat
terjadinya akulturasi dan kontak budaya yang damai ini karena masing-masing
pihak mengembangkan sikap toleran, saling menghormati dan menghargai.
Hubungan antara etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi berjalan dinamis dan
fluktuatif. Awalnya damai, kemudian mengalami konflik setelah kehadiran Belanda
di Nusantara. Akibat kebijakan pembagian kelas oleh Belanda, citra etnis Tionghoa
dalam pandangan masyarakat pribumi jadi negatif. Stereotip negatif dialamatkan
kepada mereka, dan itu berkembang dari masa ke masa. Kondisi ini diperparah
dengan kebijakan Orde Baru yang cenderung diskriminatif dan tindakan beberapa
orang Tionghoa yang melakukan korupsi dengan jumlah fantastis sehingga
merugikan Negara.
Berbagai literatur menjelaskan bahwa ada pengaruh etnis Tionghoa di berbagai
wilayah di Nusantara, termasuk Cirebon dalam hal ini Kesultanan Cirebon di satu
sisi. Sementara di sisi yang lain, Cirebon adalah kota yang sangat kosmopolitan dan
merupakan central aktivitas perdagangan di masa lalu, sehingga itu nyaris tidak
mungkin kalau tidak ada jejak etnis Tionghoa dalam kebudayaan Cirebon,
khususnya di Kesultanan Cirebon. Indikasi ke arah itu ada beberapa catatan, tetapi
sejauh ini belum menjadi perhatian para sarjana. Jadi, yang menjadi masalah dalam
penelitian ini adalah bahwa ada sesuatu yang menurut hipotesis penulis, seharusnya
pengaruh Tionghoa di Cirebon itu sangat kuat dan berjejak di dalam artefak-artefak.
Dalam konteks itu, ada dua alasan yang bisa penulis kemukakan, yakni pertama,
karena Tionghoa sangat berpengaruh di Nusantara, dan kedua karena Cirebon
menjadi kota lalu lintas ketika itu. Itu sebabnya tema ini menurut penulis penting
untuk ditelusuri dan dikaji lebih jauh lagi. Penelitian ini di samping mengelaborasi
akulturasi budaya etnis Tionghoa dan Cirebon di Kesultanan Cirebon, juga ingin
menganalisis makna simbolik dan filosofis dari hasil perwujudan budaya berupa
benda-benda bersejarah di antaranya yaitu Keraton Kasepuhan, makam Astana
Gunung Jati, Kereta Kencana Singa Barong dan batik Cirebon, serta Taman Air
Sunyaragi.
B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, secara garis besar ada beberapa hal
yang dapat diidentifikasi terkait akulturasi budaya Tionghoa dan budaya Cirebon, di
antaranya:
1) Cirebon menyimpan berbagai peninggalan arkeologis yang erat kaitannya
dengan produk yang berasal dari Tiongkok, serta letak geografisnya sebagai
bekas pelabuhan internasional memungkinkan terjadinya kontak sosial,
budaya, dan agama antara etnis Tionghoa dan Cirebon.
89
Z. Majchrzyk, “Cultural Identity and Aggression within the Acculturation Framework
of the Global World”. Sveikatos, vol. 29, no. 1, 2019, h. 56.; M. Nowak, “The Funnel
Beaker Culture in Western Lesser Poland: Yesterday and Today”. Archaeologia Polona, vol.
57, 2019.; D. S. Yu & K. M. A. Malik, “Cultural Islam in Northern Europe”. Baltic
Region, vol. 11, no. 3, 2019.
19
2) Kedatangan etnis Tionghoa ke Nusantara diawali motivasi ekonomi dan
dakwah Islam, serta adanya hubungan antara Muslim di Nusantara dengan
Muslim di Tiongkok yang dibuktikan melalui perjalanan Cheng Ho.
3) Pernikahan Sunan Gunung Jati (Sultan Cirebon) dengan Ong Tien putri
keturunan etnis Tionghoa.
4) Budaya material dan non-material di Kesultanan Cirebon dihiasi nuansa
Tiongkok, sebab sejak awal telah terbentuk hubungan dinamis antara etnis
Tionghoa dan penduduk Nusantara.
5) Politik Devide et Impera oleh Belanda, salah satunya bertujuan memecah
belah hubungan antara penduduk lokal dan etnis Tionghoa, serta adanya
stigma negatif terhadap kaum minoritas etnis Tionghoa di Indonesia.
2. Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana akulturasi budaya
Tionghoa dan Cirebon pada Kesultanan Cirebon abad XV-XVIII?. Rumusan
masalah tersebut diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan minor sebagai berikut :
a. Bagaimana aktivitas sosial-budaya etnis Tionghoa dan Cirebon di Kesultanan
Cirebon?
b. Bagaimana relasi budaya etnis Tionghoa dan masyarakat Cirebon?
c. Bagaimana makna simbolik dan filosofis dari wujud budaya Tionghoa dan
Cirebon dalam Kesultanan Cirebon?
3. Pembatasan Masalah
Agar pembahasan dalam penelitian ini fokus pada hal-hal yang seharusnya
diteliti, maka penulis membatasinya pada beberapa hal sebagai berikut:
a. Tema penelitian dibatasi pada akulturasi budaya Tionghoa dan budaya
Cirebon di Kesultanan Cirebon.
b. Objek penelitian adalah benda-benda peninggalan sebagai wujud akulturasi
etnis Tionghoa dan Cirebon (arsitektur Keraton Kasepuhan, Makam Astana
Gunung Jati, Kereta Kencana Singa Barong, Batik Cirebon, dan Taman Air
Sunyaragi).
c. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah daerah Cirebon, khususnya
Kesultanan Cirebon.
d. Penelitian ini dibatasi pada abad XV-XVIII dengan alasan bahwa bangunan-
bangunan bersejarah yang dipaparkan dibangun pada abad XV–XVIII.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi akulturasi budaya
Tionghoa dan budaya Cirebon di Kesultanan Cirebon. Adapun tujuan khususnya
adalah ingin mengungkap dan menganalisis beberapa hal sebagai berikut:
1. Mengungkap dan menganalisis aktivitas sosial-budaya Tionghoa dan Cirebon
di Kesultanan Cirebon.
2. Mengungkap dan menganalisis relasi budaya etnis Tionghoa dan masyarakat
Cirebon.
3. Mengungkap dan menganalisis makna simbolik dan filosofis dari wujud
budaya Tionghoa dan Cirebon dalam Kesultanan Cirebon.
20
D. Manfaat dan Signifikansi Penelitian
Secara teoritis maupun praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
untuk berbagai pihak, di antaranya:
a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai riset terbaru tentang kesejarahan
dan kebudayaan Nusantara dalam konteks Indonesia, khususnya terkait
budaya Tionghoa dan budaya Cirebon.
b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan atau referensi bagi
akademisi maupun peneliti, khususnya bagi para peneliti yang akan
mengkaji budaya Tionghoa dan budaya Cirebon.
c. Melalui hasil penelitian ini, informasi terkait perpaduan budaya Tionghoa
dan Cirebon dalam bentuk arkeologis dapat diketahui masyarakat secara
luas.
d. Masyarakat luas dapat memahami makna simbolis dan filosofis dari
arsitektur Keraton Kasepuhan, Makam Astana Gunung Jati, Kereta Kencana
Singa Barong, batik Cirebon, dan Taman Air Sunyaragi yang ada dalam
Kesultanan Cirebon.
e. Perpaduan budaya Tionghoa dan Cirebon yang terjadi melalui proses
akulturasi mampu menciptkan keharmonisan di antara dua budaya.
Pelajaran berharga tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat
Indonesia, khususnya masyarakat Cirebon dalam merawat keharmonisan di
tengah keberagaman.
f. Nilai-nilai dibalik perwujudan budaya dapat dijadikan sebagai bentuk
akulturasi yang baik, seperti sikap saling menghormati, menghargai dan
menerima perbedaan.
g. Mendorong masyarakat mampu memelihara dan mengamalkan budaya yang
mengandung nilai-nilai toleransi sehingga terwujud tatanan hidup yang
rukun dan damai di Indonesia, khususnya di daerah Cirebon maupun di
dalam Kesultanan.
h. Sebagai bangsa yang majemuk pemahaman tentang akulturasi menjadi
penting agar tercipta kebebasan, keadilan dan perdamaian.
i. Penelitian ini diharapkan mendapat perhatian dari pihak pemerintah yang
bersangkutan untuk dapat terus menjaga nilai-nilai historis yang masih
tersimpan di keraton, terutama menjaga dan merawat budaya-budaya
material dan non-material yang menyimpan nilai historis, selain sebagai aset
di bidang pariwisata juga sebagai aset pendidikan bagi generasi mendatang.
E. Kajian Terdahulu yang Relevan
Budaya Tionghoa dan budaya Cirebon, maupun perpaduan di antara kedua
budaya tersebut telah ikut mewarnai budaya-budaya yang ada di Nusantara
termasuk Indonesia atau khususnya Cirebon. Menurut penelusuran penulis, kajian
tentang budaya Nusantara di Indonesia khususnya budaya Tionghoa dan budaya
Cirebon telah diteliti dan ditulis oleh banyak kalangan dari berbagai perspektif yang
berbeda-beda, di antaranya:
21
De Graaf dan Pigeaud, Chinese Muslim in Java in The 15 th And 16 th
Centuries: The Malay Annals of Semarang and Cerbon.90
De Graaf dan Pigeud
memasukkan naskah yang dikenal dengan nama The Malay Annals of Semarang
and Cerbon. Sebuah naskah yang menarik juga penuh teka-teki. Naskah ini
mengajak kita kepada kebingungan sejarah atau bahkan ke dalam fantasi sejarah.
Ricklefs yang mengedit buku ini, di satu sisi mengakui upaya dari kedua penulis,
tetapi di sisi lain mempertanyakan keaslian Sejarah Melayu. Bahkan, Lombard91
juga meragukan keberadaannya, dan karenanya menolak gagasan bahwa sebagian
besar Wali adalah Tionghoa peranakan. Meskipun demikian, Lombard dan Salmon,
melalui karya mereka “Islam and Chineseness”92
tetap mengakui adanya peran
Muslim Tionghoa di Jawa. Menurut mereka, Tionghoa Muslim peranakan memiliki
peran penting dalam proses islamisasi di Jawa. Mereka juga menyebut bahwa
banyak di antara saudagar Tionghoa Muslim yang dipekerjakan di kota-kota utama
pesisir Jawa oleh penguasa setempat, bahkan juga di pelabuhan-pelabuhan luar
Jawa. Pada perkembangannya banyak di antara mereka yang melakukan perkawinan
dengan wanita lokal, baik wanita bangsawan maupun wanita dari keturunan biasa.
Hubungan ini juga memengaruhi berbagai budaya Nusantara, seperti ukiran masjid
Jepara yang punya undak 5 sepintas seperti pagoda, juga memengaruhi bidang
sastra.
Weng, Berislam Ala Tionghoa: Pergulatan Etnisitas dan Religiusitas di
Indonesia.93
Dalam bukunya Hew menganalisis identitas budaya Tionghoa Muslim
sebagai bagian dari Islam Indonesia dengan cara memaparkan tentang negosiasi
identitas yang terus berlangsung di antara adat atau tradisi Islam Indonesia yang
beragam. Menurutnya orang dapat menjadi islami tanpa harus menanggalkan
budaya Tionghoa, begitu juga orang dapat menjadi lebih Indonesia dengan tetap
mempertahankan budaya Tionghoa. Manifestasi identitas budaya Tionghoa Muslim
menunjukkan bahwa perjumpaan antara religiusitas keislaman yang terus tumbuh
dan keragaman budaya yang berkembang di Indonesia telah melahirkan sebuah
kesalehan Islam yang tegas sekaligus inklusif.
Karya penting lainnya yang membahas hubungan Tiongkok-Indonesia adalah
yang ditulis Tanggok, Menghidupkan Kembali Jalur Sutra Baru: Format Baru
Hubungan Islam Indonesia dan China”.94
Tanggok berusaha mengurai kembali
hubungan antara Tiongkok-Indonesia. Menurutnya, secara historis hubungan di
antara keduanya telah terjadi sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum
kedatangan penjajah Belanda. Hubungan yang terjalin sangat harmonis dan
90
H. J. de Graaf & Th. G. Th. Pigeaud, Chinese Muslim in Java in The 15 th And 16 th
Centuries: The Malay Annals of Semarang and Cerbon. Edited by M. C. Ricklefs
(Melbourne: Monash University, 1984). 91
D. Lombard, “H. J. de Graaf & Th. G. Th. Pigeaud, Chinese Muslims in Java in the
15th and 16th Centuries”. Archipel, vol. 32, no. 1, 1986, h. 186-187. 92
D. Lombard & C. Salmon, “Islam and Chineseness”. Indonesia, no. 57, 1993, h. 115-
131. 93
H. W. Weng, Berislam Ala Tionghoa: Pergulatan Etnisitas dan Religiusitas di
Indonesia, (Jakarta: Mizan, 2019). 94
Ikhsan Tanggok, Menghidupkan Kembali Jalur Sutra Baru: Format Baru Hubungan
Islam Indonesia dan China”, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010).
22
mengalami kemajuan yang luar biasa. Hubungan tersebut bukan saja secara
diplomatik, tetapi juga di luar diplomatik. Karya Tanggok membawa pembaca
untuk melihat sejarah hubungan Indonesia dan Tiongkok di masa lampau, maka
sepatutnya masyarakat Indonesia saat ini meningkatkan kembali hubungan tersebut
ke arah yang lebih baik dan dikembangkan ke berbagai aspek kehidupan, terutama
dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Menurut Tanggok, jika kerja
sama di antara Tiongkok-Indonesia bisa terwujud, maka dapat dikatakan sebagai
upaya “Meretas Jalan Sutra Baru” yang berbeda dengan “Jalan Sutra Masa Lalu”.
Hoadley, “Javanese, Peranakan, and Chinese Elites in Cirebon: Changing
Ethnic Boundaries”.95
Penelitian Hoadley bagi penulis cukup menarik dimana ia
mencoba meninjau kembali batas etnis antara elit Jawa, Tionghoa peranakan, dan
Tionghoa di Cirebon. Menurut penelitiannya, ada tiga fase yang dapat dilihat dalam
pengembangan hubungan etnis di Cirebon selama periode 1680-1731. Sampai
dekade pertama abad ke-18, menurut norma-norma Jawa ada dua kelompok elit:
Jawa, termasuk peranakan yang baru direkrut, dan Tionghoa. Meskipun dibedakan
oleh identitas yang terpisah dan fungsi sosial khusus, kelompok-kelompok tersebut
pada awalnya terbuka dalam gerakan yang melintasi batas-batas etnis yang
sepenuhnya dapat diterima. Kemudian fase kedua di antar oleh tindakan para
pejabat Belanda, yang sejak awal pemerintahan kolonial di Cirebon telah berusaha
mengidentifikasi peranakan sebagai etnis Tionghoa dengan penggunaan istilah
Melayu peranakan atau, yang lebih umum, peranakan Tionghoa. Pada dekade
pertama abad ke-18, Belanda giat mengambil langkah-langkah aktif untuk
memisahkan mereka yang mereka identifikasi sebagai peranakan dari elit Jawa
dengan melarang pekerjaan mereka sebagai menteri Cirebon dan memastikan
bahwa perkebunan mereka ditangani oleh boedelmeester Tionghoa. Puncak logis
dari fase perkembangan ini adalah pemindahan semua peranakan ke otoritas pejabat
kompeni, Kapitan Tionghoa. Mereka berharap menciptakan situasi etnis di mana
orang Jawa terpisah dari etnis Tionghoa peranakan.
Fase ketiga dan terakhir terdiri dari reaksi para pangeran Cirebon selama
periode 1720-1731, yang mencegah rencana Belanda menjadi kenyataan. Motivasi
pangeran untuk oposisi datang dari kebutuhan mereka untuk mencegah hilangnya
sumber daya tenaga kerja dan layanan dari kelompok yang telah menyediakan
banyak pejabat tinggi mereka selama setengah abad. Tetapi keinginan mereka untuk
mencegah Belanda dari memasukkan peranakan di bawah Kapitan Tionghoa
memaksa para pangeran Cirebon untuk membuat perbatasan antara orang
Jawasekarang secara khusus termasuk peranakandan Tionghoa. Pertahanan
Jawa atas sumber daya manusia terhadap perambahan Belanda menghasilkan batas-
batas etnis yang membatu dari jenis yang sebelumnya tidak diketahui di Cirebon.
Namun, dalam analisis akhir Hoadley, tindakan para pangeran pada 1720-1731
kurang eksklusif secara etnis daripada perpecahan antara Jawa dan peranakan/
Tionghoa yang akan menghasilkan jika pengajuan Belanda di tahun 1730 telah
menjadi kenyataan. Akhir dari periode 1731 merupakan setengah jalan antara situasi
di Jawa kolonial dan yang di Thailand non kolonial. Hasil tindakan Kompeni Hindia
95
M. C. Hoadley, “Javanese, Peranakan, and Chinese Elites in Cirebon: Changing
Ethnic Boundaries.” The Journal of Asian Studies, vol. 47, no. 3, 1988, h. 503-517.
23
Timur Belanda negatif dalam arti ganda. Mereka mengurangi insentif untuk
integrasi dengan merongrong otoritas elit Jawa dan menghilangkan hadiah untuk
integrasi dalam bentuk pos pengadilan. Hanya dalam abad-abad berikutnya,
langkah-langkah yang diambil secara aktif untuk mendorong orang-orang yang
berasal dari Tiongkok untuk mengidentifikasi diri dengan elit kolonial.
Muhaimin, “The Islamic Traditions of Cirebon: Ibadat and Adat Among
Javanese Muslims”.96
Muhaimin membahas keyakinan masyarakat Cirebon hingga
apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka berperilaku. Menurutnya apa yang
mereka yakini memotivasi apa yang mereka perbuat, dan apa yang mereka lakukan
mencerminkan ungkapan verbal apa yang mereka yakini. Muhaimin menemukan
bahwa semua tradisi yang berkembang dalam masyarakat Cirebon juga dapat
ditemukan dalam tradisi Islam yang berakar pada wahyu atau mendapatkan
pembenaran dalam literatur hukum Islam, baik yang bersumber dari al-Qur‟an,
hadis maupun fikih para ulama.
Darheni, “The Language Characteristic and Its Acculturation from Chinese
Speakers in Losari, Cirebon Regency, West Java: The Acculturation of Chinese
with Javanese Culture”.97
Darheni mengkaji tentang akulturasi bahasa dan budaya
Tionghoa di Losari, Cirebon. Penelitiannya menemukan bahwa situasi linguistik di
Cirebon adalah diglossic. Di Cirebon menurut temuan Darheni sejumlah bahasa
digunakanbahasa Cirebon, bahasa Sunda Cirebon, bahasa Indonesia, dan bahasa
asing seperti bahasa Arab, Tionghoa, Belanda, dan Inggris. Hokkian adalah salah
satu bahasa yang digunakan secara produktif oleh komunitas etnis Tionghoa di
Losari, Cirebon (perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah). Akulturasi bahasa
dan budaya antara kelompok etnis Tionghoa dan kelompok asli dapat dilihat dari
difusi yang jelas dalam cara berpikir dan perilaku kedua kelompok etnis di wilayah
tersebut. Selain itu, temuan penting Darheni menurut penulis adalah bahwa
primordialisme antara kelompok etnis asliCirebon dan Tionghoa tidak terlihat
jelas. Menurutnya, yang menunjukkan pembentukan komunikasi adalah dalam
aspek sosial, ekonomi, pemerintahan, dan kekuasaan. Akibatnya, akulturasi bahasa
Mandarin dengan budaya Jawa di Cirebon Timur mencakup aspek fonologis,
leksikal atau diksi (yang paling sering), morfologis (paling unik), dan sintaksis.
Al Qurtuby, Arus Cina-Islam-Jawa: Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa
dalam Penyebaran Agama Islam di Indonesia Abad XV & XVI.98
Karya Al Qurtuby
96
A. G. Muhaimin, “The Islamic Traditions of Cirebon: Ibadat and Adat Among
Javanese Muslims”. (Unpublished PhD Thesis, The Australian National University,
Canberra, 1995). Tesis Muhaimin ini kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berbahasa
Indonesia, lihat A. G. Muhaimin, Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon,
(Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2002). 97
N. Darheni, “The Language Characteristic and Its Acculturation from Chinese
Speakers in Losari, Cirebon Regency, West Java: The Acculturation of Chinese with
Javanese Culture”. In The 1st International Seminar on Language, Literature and
Education, KnE Social Sciences, 2018, h. 663-686. 98
S. Al Qurtubi, Arus Cina-Islam-Jawa: Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa
dalam Penyebaran Agama Islam di Indonesia Abad XV & XVI, (Yogyakarta: Inspeal
Ahimsya Karya Press, 2003).; Lihat juga S. AI Qurtuby, “The Tao of Islam: Cheng Ho and
24
berupaya menegaskan bahwa Tionghoa Muslim pada faktanya telah ikut
membentuk apa yang selanjutnya disebut sebagai “Sino-Javanese Muslim Culture”,
sebuah proses akulturasi antara budaya Tionghoa, Islam dan Jawa. Bentuk “Sino-
Javanese Muslim Culture” itu tidak hanya tampak dalam berbagai bangunan
peribadatan Islam yang menunjukan adanya unsur Jawa, Islam, Tionghoa tetapi juga
berbagai seni/sastra (batik, ukir) dan unsur kebudayaan lain. Al Qurtuby
menemukan bahwa dari berbagai literatur Tionghoa, Iiteratur lokal Jawa, tradisi
Iisan, serta berbagai peninggalan purbakala Islam dalam kurun abad ke-15/16
mengisaratkan pengaruh Tionghoa di Jawa sangat terasa. Ukiran padas di masjid
kuno Mantingan Jepara, menara masjid pecinaan Banten, konstruksi pintu makam
Sunan Giri di Gresik, arsitektur Keraton Cirebon beserta Taman Sunyaragi,
konstruksi masjid Demak, khususnya soko tatal penyangga masjid beserta lambang
kura-kura, konstruksi masjid sekayu di Semarang, ataupun masjid Kali Angke dan
Masjid Kebun Jeruk di Jakarta, setidaknya dapat menjadi landasan asumsi tersebut.
Tanpa mengesampingkan keterlibatan Tionghoa Muslim lainnya, Al Qurtuby
mengatakan tokoh yang berperan bagi terjalinnya proses tersebut adalah Cheng Ho.
Penting dicatat bahwa Cheng Ho ikut serta dalam menyiarkan ajaran agama Islam
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang selanjutnya ia kombinasikan dengan
beberapa prinsip ideal yang diadopsi dari ajaran lokal Tionghoa seperti
Konfusiusme maupun Taoisme. Di sinilah menurut Al Qurtuby titik singgung
terkait relasi antara Islam sebagai agama lokal Indonesia dengan beberapa prinsip
Tao sebagai kepercayan lokal Tionghoa bisa diidentifikasi.
Dyah dan Zein, “The Influence of Cultural Acculturation on Architecture
Keraton Kasepuhan Cirebon”.99
Temuan penting dari penelitian Dyah dan Zein
mengatakan bahwa akulturasi terbukti dalam arsitektur bangunan, yang
menunjukkan pengaruh budaya asing Eropa dan Tiongkok, serta Hinduisme lokal
dan budaya Jawa. Akulturasi di Keraton Kasepuhan Cirebon diterapkan pada
beberapa elemen arsitektur. Elemen arsitektur struktur bangunan ditemukan pada
pilar dan atap bangunan. Unsur non arsitektur dari struktur bangunan, akulturasi
budaya dapat ditemukan pada lengkungan, dinding, pintu dan jendela. Sementara
elemen arsitektur dekoratif bangunan, akulturasi budaya ditemukan pada hiasan
dinding dan patung.
Dewi dan Annisa, “Akulturasi Budaya pada Perkembangan Kraton Kasepuhan
Cirebon”.100
Temuan penelitian mereka mengatakan akulturasi budaya pada Kraton
Kasepuhan Cirebon terjadi karena pengaruh lokasi yang strategis dan sikap yang
terbuka dari Sultan Cirebon. Hal tersebut menjadikan Cirebon sebagai pusat
perdagangan, tempat bertemunya berbagai suku, agama, dan budaya antar bangsa.
Lebih jauh dikemukakan bahwa sikap terbuka dari Sultan Cirebon merupakan poin
the Legacy of Chinese Muslims in Pre-Modern Java”. Studia Islamika, vol. 15, no. 1, 2009,
h. 51-78. 99
S. A. Dyah & F. K. Zein, “The Influence of Cultural Acculturation on Architecture
Keraton Kasepuhan Cirebon”. In Reframing the Vernacular: Politics, Semiotics, and
Representation, (Cham: Springer, 2020), h. 251-260. 100
H. I. Dewi dan Anisa, “Akulturasi Budaya pada Perkembangan Keraton Kasepuhan
Cirebon”. Proceeding PESAT Universitas Gunadarma Depok, vol. 3, 2009.
25
penting masuknya beberapa pengaruh budaya asing, seperti budaya Tionghoa,
Hindu, Buddha, Jawa, Eropa, Islam dan Arab dalam masyarakat Cirebon, terutama
pada bangunan Kraton Kasepuhan. Penelitian mereka secara spesifik menyebutkan
budaya Tionghoa dapat ditemukan pada bangunan Dalem Agung Pakungwati, Siti
Inggil (termasuk Mande Pendawan, Mande Semar Tinandu, Mande Kresman,
Mande Pengiring), Kucung Kutagara Wadasan dan pintu Buk Bacem; pengaruh
Hindu pada Siti Inggil; pengaruh Buddha pada Bangsal Prabayaksa; pengaruh Jawa
pada tiang-tiang Mande Semar Tinandu, Mande Pengiring, Jinem Pangrawit;
pengaruh Eropa pada Pungkuran, Jinem Pangrawit, Bangsal Prabayaksa, Gajah
Nguling; pengaruh Arab dapat ditemukan pada pintu Buk Bacem. Terakhir,
pengaruh Islam dapat ditemukan pada Mande Malang Semirang.
Beberapa karya terdahulu di atas patut diapresiasi, sebab keberadaannya
membuka ruang dan jalan bagi penulis untuk melihat permasalahan yang dikaji agar
lebih komprehensif. Karya de Graaf dan Pigeaud, meskipun mendapat kritikan dari
Ricklefs dan Lombard karena seolah berlebihan atas gagasan mereka bahwa
sebagian besar Wali adalah Tionghoa peranakan. Namun, Karya de Graaf dan
Pigeaud membantu penulis dalam mengidentifikasi peran Tionghoa Muslim, baik
dalam konteks Cirebon maupun Indonesia pada umumnya. Sebagaimana juga karya
Tanggok bahwa secara historis hubungan Tionghoa dan Indonesia telah terjadi
sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum kedatangan penjajah Belanda.
Hubungan yang terjalin sangat harmonis dan mengalami kemajuan yang luar biasa.
Hubungan tersebut bukan saja secara diplomatik, tetapi juga di luar diplomatik.
Juga yang menjadi perhatian penulis adalah karya Weng yang menganalisis
identitas budaya Tionghoa Muslim sebagai bagian dari Islam Indonesia. Menurut
penulis karya-karya yang disebutkan adalah karya penting untuk melihat sisi lain
sejarah awal perkembangan Islam di Nusantara, termasuk dalam melihat peran
Tionghoa Muslim dalam konteks Indonesia dan Cirebon, sebelum penulis
mengungkapkan makna-makna simbolik dan filosofis yang luput dari karya mereka.
Penulis belum menemukan satu kajian yang secara mendalam mengkaji makna
simbolis dan filosofis dari wujud budaya material etnis Tionghoa dan Cirebon di
Kesultanan Cirebon. Muhaimin misalnya, ia lebih banyak berbicara tentang budaya
non material, khususnya tradisi Islam yang mencakup ibadah dan adat masyarakat.
Fokus inilah yang membedakan antara penelitian Muhaimin dengan penelitian yang
penulis lakukan. Disamping itu, penulis melihat kajiannya Muhaimin seolah
“menampik” kontribusi dari unsur-unsur di luar Islam seperti Hindu, Buddha dan
sebagainya. Padahal, kalau kita lihat berbagai benda peninggalan (budaya material),
khususnya di Kesultanan Cirebon juga dapat ditemukan secara jelas adanya
pengaruh dari luar Islam, seperti Hindu, Tionghoa dan sebagainya. Begitupun
Darheni yang mengkaji soal ciri bahasa dan akulturasi dari penutur bahasa
Tionghoa di Cirebon. Darheni lewat temuannya mengatakan bahwa primordialisme
antara kelompok etnis asliCirebon dan Tionghoa tidak terlihat jelas, tetapi
signifikansi yang menunjukkan pembentukan komunikasi (bahasa) adalah pada
aspek sosial, ekonomi, pemerintahan dan kekuasaan. Penting dicatat bahwa selain
dari aspek bahasa (budaya non material), aspek budaya material berupa benda-
benda peninggalan di Kesultanan Cirebon juga penting diungkap karena di
dalamnya tersimpan makna simbolis dan filosofis yang sampai sekarang tidak henti-
26
hentinya dikaji dan dibicarakan. Wujud budaya atau budaya material tersebut
semacam mengajak kita untuk membahasakan apa yang dikandungnya, utamanya
yang berkaitan dengan aspek sejarah masalah lalu. Dengan demikian, penelitian ini
sebagai tidak lanjut atau memperkaya penelitian sebelumnya dengan menyajikan
perspektif baru dalam konteks akulturasi etnis Tionghoa dan Cirebon, sehingga
lebih komprehensif. Argumentasi dan komentar penulis terhadap penelitian
Muhaimin dan Darhenni juga mendapat dukungan dari Al Qurtuby dengan
meminjam apa yang ia sebut “Sino-Javanese Muslim Culture”itu tidak hanya
tampak dalam berbagai bangunan peribadatan Islam yang menunjukan adanya unsur
Jawa, Islam, Tionghoa tetapi juga berbagai seni/sastra (batik, ukir) dan unsur
kebudayaan lain.
Selain temuan Muhaimin dan Darheni, penelitian Hoadley di atas cukup
membantu penelitian ini sebelum masuk dan menjawab bagaimana wujud budaya
etnis Tionghoa dan Cirebon, utamanya dalam mengungkap makna simbolis dan
filosofisnya. Penelitian Hoadley nantinya membantu penulis dalam pencarian
definisi internal etnis yang valid secara lokal, sehingga mengurangi bahaya
kontaminasi nilai atau determinisme historis dari pihak luar, baik itu pengamat asing
kontemporer atau peneliti modern. Jika kita menerima pengamatan pejabat kolonial
Belanda tanpa kritik, menurut Hoadley kita dapat dengan mudah salah memahami
dasar kerja sama antara Tiongkok dan Jawa, bahkan di Cirebon, para menteri
Muslim untuk para pangeran diterima karena mereka telah menjadi orang Jawa;
pejabat Tionghoa, syabbandar dan Kapitan Tionghoa, tetap asing dengan sistem
sosial mayoritas. Pendekatan ini juga membutuhkan perhatian terhadap perubahan
seiring waktu. Dalam contoh ini, Hoadley mengatakan hanya etnis Tionghoa dan
Jawa yang ada pada awalnya, tetapi asumsi kekuasaan Belanda membawa
kelompok etnis ketiga, dengan batas-batas yang dapat dikenali, terbentuk setelah
1730. Kelompok ini adalah peranakan, sampai saat itu kategori deskriptif hanya
digunakan oleh orang Belanda. Hoadley menggunakan seperti apa yang disarankan
Skinner, konsekuensi penting dari perkembangan ini adalah bahwa hubungan etnis
yang tidak harmonis di Jawa modern adalah produk, bukan hanya datum, sejarah.
Dari sekian penelitian terdahulu yang penulis kemukakan di atas, ada dua
penelitian yang mirip dengan penelitian ini, yang fokus pada akulturasi budaya
material yang ada di Keraton Kasepuhan, yakni penelitian Dyah dan Zein, serta
penelitian Dewi dan Annisa. Penelitian mereka membantu penulis dalam
mengidentifikasi budaya-budaya Tionghoa yang ada di Keraton Kasepuhan, namun
penulis melihat mereka kurang mengeksplorasi terkait dengan budaya Cirebon itu
sendiri. Inilah salah satu pembeda dengan penelitian ini. Selain itu, karya mereka
hanya sekadar menyebutkan adanya pengaruh budaya dari luar yang terakulturasi
dengan Keraton Kasepuhan. Berbeda dengan penelitian ini, penulis berangkat dari
menentukkan beberapa pengaruh budaya yang terakulturasi dengan budaya Cirebon,
khususnya budaya dari luar yang masuk ke dalam Keraton Kasepuhan, kemudian
mengungkapkan makna-makna simbolik dan filosofis secara mendalam. Di
samping, sebelumnya penulis juga memerhatikan perkembangan daerah dan
masyarakat Cirebon serta Kesultanan Cirebon yang menjadi bagian penting dari
penelitian ini.
27
F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pedekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sementara jenis penelitiannya
adalah kepustakaan dan lapangan, sebab data-datanya tidak hanya bersumber dari
literatur tetapi juga data lapangan berupa pengamatan dan wawancara. Metode dan
jenis penelitian tersebut digunakan sebagai suatu payung konsep meliputi beberapa
format penelitian yang membantu penulis dalam memahami dan menjelaskan
makna fenomena sosial dari setting alamiah101
yang ada sebagaimana Moleong
mengatakan jenis penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami.102
Secara komprehensif penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan Creswell
adalah suatu proses penelitian ilmiah yang dimaksudkan untuk memahami masalah-
masalah manusia dalam konteks sosial. Dengan menciptakan gambaran menyeluruh
dan kompleks, kemudian disajikan dengan melaporkan pandangan terperinci dari
sumber informasi, serta dilakukan dalam setting alamiah tanpa adanya intervensi
dari peneliti.103
Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis
dan antropologis yaitu penelitian ilmiah yang didasarkan pada kajian sejarah yang
berbasis pada kajian kepustakaan dan telaah data dengan berpegang teguh pada
norma atau kaidah yang berlaku. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan
semiotik104
untuk menganalisa makna simbolik dan filosofis dari wujud relasi
budaya Tionghoa dan Cirebon.
Saussure mengartikan semiotika sebagai ilmu yang mengkaji tanda sebagai
bagian dari kehidupan sosial.105
Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda
(sign), berfungsinya tanda dan produksi makna. Tanda adalah sesuatu yang bagi
seseorang berarti sesuatu yang lain, dan tidak hanya berbentuk sebuah benda.
Dalam kehidupan manusia, tanda selalu menyampaikan suatu informasi sehingga
mempunyai sifat komunikatif.106
Artinya, satu kata dalam kajian semiotika memiliki
makna tertentu disebabkan adanya kesepakatan sosial di antara komunitas pengguna
bahasa tentang makna.107
101
S. B. Mariam, Qualitative Research and Case Study Application in Education, (San
Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 1998), h. 5. 102
L. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 1995), h.
25. 103
J. W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed,
(Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998). 104
D. Hattenhauer, “The Rhetoric of Architecture: A Semiotic
Approach”. Communication Quarterly, vol. 32, no. 1, 1984, h. 71-77.; M. Gottdiener,
“Hegemony and Mass Culture: A semiotic approach”. American Journal of Sociology, vol.
90, no. 5, 1985, h. 979-1001. 105
F. de Saussure, “Course in General Linguistics”, In Literary Theory, An Anthology,
by J. Rivkin & M. Ryan (eds.), (UK: Blackwell Publishing Ltd., 2004), h. 59-71. 106
H. S. M. Yakin & A. Totu, “The Semiotic Perspectives of Peirce and Saussure: A
Brief Comparative Study”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 155, 2014, h. 4-8. 107
J. Kristeva, Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art, (New
York: Columbia University Press, 1980), h. 31.
28
Adapun tahapan analisis data diawali dengan pengambilan data (collecting
data) yang berkaitan dengan budaya Tionghoa dan Cirebon, serta sejarah dari
keduanya. Kemudian, penulis melakukan observasi dan wawancara langsung
dengan para informan dengan berpedoman pada pedoman observasi dan wawancara
yang telah disusun pada tahap pendahuluan untuk memperdalam data atau informasi
yang diperoleh. Setelah data dikumpulkan, penulis kemudian mengklasifikasi dan
menganalisa data tersebut, serta membuat kesimpulan berupa jawaban-jawaban atas
masalah-masalah yang menjadi inti penelitian. Terakhir adalah penyusunan hasil
penelitian dan pelaporannya yang disusun dalam kerangka yang sistematis dan
logis.
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer
diambil dari para narasumber (filolog, sejarawan, budayawan dan pihak Kesultanan
Cirebon). Penulis memilih narasumber dari tokoh-tokoh yang dianggap mengetahui
agar bisa memberikan informasi sesuai data yang dibutuhkan. Sementara data
sekunder, yakni telaah dari berbagai literatut seperti buku, arsip, jurnal, dan laporan
penelitian yang tentu relevan dengan kajian ini.
3. Instrumen Pengumpulan Data
Langkah dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu: pertama,
observasi.108
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang
spesifik karena observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam
yang lain. Kedua, wawancara.109
Wawancara menjadi teknik yang penting selain
observasi dalam proses pengumpulan data karena ternyata masih banyak data-data
yang masih berada dalam ingatan pelaku atau pegiat budaya Cirebon, termasuk
tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama Ketiga, pencatatan. Pencatatan ini
dilakukan pada saat wawancara berlangsung dan setelah wawancara. Pencatatan ini
dilakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan data sesuai kebutuhan yang
diperlukan peneliti. Keempat, dokumentasi.110
Semua dokumentasi, baik gambar
maupun keterangan yang berkaitan dengan penelitian digunakan guna melengkapi
catatan hasil observasi dan wawancara.
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data
108
C. Pope & D. Allen, “Observational Methods”. Qualitative Research in Health Care,
2020, h. 67-81.; J. Rose & C. W. Johnson, “Contextualizing Reliability and Validity in
Qualitative Research: Toward More Rigorous and Trustworthy Qualitative Social Science in
Leisure Research”. Journal of Leisure Research, 2020, h. 1-20. 109
Chien-Juh Gu, “Qualitative Interviewing in Ethnic-Chinese Contexts: Reflections
From Researching Taiwanese Immigrants in the United States”. International Journal of
Qualitative Methods, vol. 19, 2020. 110
J. Pakkanen, A. Brysbaert, D. Turner, & Y. Boswinkel, “Efficient three-dimensional
field documentation methods for labour cost studies: Case studies from archaeological and
heritage contexts”. Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, vol. 17,
2020, h. 1-10.
29
Seluruh data yang berhasil dikumpulkan melalui beberapa teknik pengumpulan
di atas, peneliti kemudian mencatat ulang semuanya untuk dijadikan sebagai catatan
lapangan. Data tersebut kemudian diolah dengan cara reduksi data melalui proses
inklusi dan eksklusi. Proses inklusi adalah mengambil data yang relevan dengan
penelitian, sedangkan proses eksklusi adalah membuang data yang tidak relevan.
Kemudian peneliti melakukan proses coding atau pemberian kode agar sumber
datanya tetap dapat ditelusuri dengan mudah dan cepat.langkah berikutnya, catatan-
catatan yang telah diberi kode tersebut diedit (editing) dengan cara dipilah-pilah,
diklasifikasi, disintesiskan dan dibuat ikhtisarnya. Langkah berikutnya penulis
melakukan pemaknaan terhadap data-data tersebut. Data yang diperoleh dianalisis
kemudian dideskripsikan secara kualitatif. Metode kualitatif deskriptif adalah
menggambarkan dan memaparkan data hasil penelitian, baik yang bersumber dari
wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan berupa kalimat-kalimat atau
paragraf-paragraf bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.
Analisa kualitatif digunakan untuk menganalisis proses sosial yang berlangsung dan
makna dari fakta-fakta yang tampak dipermukaan itu. Dengan demikian, maka
analisis kualitatif digunakan untuk memahami sebuah proses dan fakta dan bukan
sekedar untuk menjelaskan fakta tersebut.111
Teknik analisis deskriptif dilakukan dalam tiga siklus (reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan). Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul
dari catatan tertulis di lapangan. Selama kegiatan pengumpulan data berlangsung,
dilakukan analisis data. Proses analisis data meliputi: 1) menetapkan fokus
penelitian. 2) menyusun temuan-temuan data yang diperoleh. 3) membuat rencana
pengumpulan data berikutnya sesuai temuan-temuan dari data yang dikumpulkan
sebelumnya. 4) mengembangkan pertanyaan untuk pengumpulan data berikutnya. 5)
menggali sumber-sumber kepustakaan yang berhubungan dengan pemanfaatan
media para profesional.112
Penulis menyajikan data tersebut dalam jenis penelitian
kualitatif-deskriptif, karena data yang diteliti adalah data verbal yang tidak
berbentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kata, kalimat, dan ungkapan-ungkapan
yang tertuang dalam naskah atau teks. Kemudian pada bagian akhir adalah
penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara deduktif, yaitu memulai analisis
dari hal-hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.
G. Sistematika Pembahasan
Secara umum studi tentang akulturasi budaya Tionghoa dan Cirebon di
Kesultanan Cirebon terdiri dari enam bab pembahasan. Bab I adalah bab
111
H. Kyngäs, “Qualitative Research and Content Analysis” In The Application of
Content Analysis in Nursing Science Research, (Cham: Springer, 2020), h. 3-11.; C. S.
Barroso, A. E. Springer, C. M. Ledingham, & S. H. Kelder, “A Qualitative Analysis of the
Social And Cultural Contexts that Shape Screen Time Use in Latino Families Living on the
US-Mexico Border”. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-
being, vol. 15, no. 1, 2020, h. 1735766. 112
M. Islam, “Data Analysis: Types, Process, Methods, Techniques and Tools”.
International Journal on Data Science and Technology, vol. 6, no. 10, h. 2020.
30
pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah,
perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II
adalah bab yang membahas soal interaksi budaya Tionghoa, Nusantara dan Islam.
Bab ini mendiskusikan konsep budaya secara umum yang mencakup teori
akulturasi, asimilasi dan difusi; kedatangan etnis Tionghoa: jejak Cheng Ho dan
Muslim Tionghoa; pra kolonial: Muslim Tionghoa sebagai budaya hibrida; dan
bagian terakhir bab ini membahas kemunduran budaya Muslim Tionghoa-Jawa di
era Kolonial Belanda. Bab III adalah bab yang membahas sejarah Kesultanan
Cirebon. Secara spesifik bab ini mengurai profil kesultanan, dialektika politik dan
Islam, serta perkembangan masyarakat Cirebon mulai dari sejarah Daerah Cirebon,
masuknya etnis Tionghoa ke Cirebon, Daerah Cirebon dalam lintas dagang, serta
Cirebon sebagai basis syiar Islam. Bab IV adalah bab yang membahas relasi sosial-
budaya etnis Tionghoa dan masyarakat Cirebon yang secara spesifik mengurai
beberapa poin menyangkut budaya Cirebon, corak budaya Tionghoa, serta
pergumulan budaya Tionghoa dengan budaya Cirebon. Bab V adalah bab analisis
tentang budaya Tionghoa dan Cirebon. Secara spesifik bab ini membahas tentang
makna simbolik dan filosofis dari arsitektur Keraton Kasepuhan, Kereta Kencana
Singa Barong, Batik Cirebon dan Guha Sunyaragi. Bab VI adalah bab penutup yang
berisi tentang kesimpulan dan saran, serta dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai
rujukan.
31
BAB II
INTERAKSI BUDAYA: TIONGHOA, NUSANTARA DAN ISLAM
A. Konsep Kebudayaan: Akulturasi, Asimilasi dan Difusi
Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta buddhayahbentuk jamak
dari buddhi (budi atau akal).1 Kebudayaan secara sederhana dapat diartikan sebagai
hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Para sarjana kemudian membedakan istilah
“budaya” dan “kebudayaan”. Budaya didefinisikan sebagai cipta, karsa dan rasa,
sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa.2 Dalam diskursus
antropologi budaya, perbedaan definisi antara budaya dan kebudayaan itu
ditiadakan, di mana kata “budaya” hanya dipakai sebagai suatu singkatan dari
“kebudayaan”, namun keduanya memiliki arti yang sama. Sementara “kebudayaan”
dalam literatur Inggris disebut culturedari kata Latin colere yang berarti
mengolah atau mengerjakan.3 Selain istilah “kebudayaan” (culture), dikenal juga
istilah “peradaban” (civilization)digunakan untuk menyebut unsur kebudayaan
yang halus, maju dan indah seperti kesenian, ilmu pengetahuan, norma pergaulan,
kepandaian menulis, organisasi kenegaraan dan sebagainya.4 Istilah “peradaban”
juga sering digunakan untuk menyebut kebudayaan yang mempunyai sistem
teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa dan sistem kenegaraan dari
masyarakat kota yang maju dan kompleks.5
Dalam khazanah keislaman ada „urf atau „adah yang biasa disinonimkan
dengan budaya. „Urf adalah kebiasaan dan prilaku masyarakat dalam menjalani
kehidupan sehari-hari yang kemudian dijadikan adat-istiadat turun temurun, baik
ucapan maupun perbuatan. Karena „urf merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari manusia, maka para ahli menempatkan „urf sebagai salah satu instrumen dalam
1M. Susi, D. A. Purnama, I. Nany, A. Prima & R. Krasnobaev, “Cultural
Sciences”. Cultural Sciences, vol. 34, no. 3, 2019. 2D. Saleebey, “Culture, Theory, and Narrative: The Intersection of Meanings in
Practice”. Social Work, vol. 39, no. 4, 1994, h. 351-359.; H. C. Triandis & D. P. S. Bhawuk,
“Culture Theory and the Meaning of Relatedness”. In P. C. Earley & M. Erez (eds.), The
New Lexington Press Management and Organization Sciences Series and New Lexington
Press Social and Behavioral Sciences Series. New Perspectives on International
Industrial/Organizational Psychology, (The New Lexington Press/Jossey-Bass Publishers,
1997), h. 13–52. 3D. P. Bhawuk, “The Role of Culture Theory in Cross-cultural Training: A
Multimethod Study of Culture-specific, Culture-general, and Culture Theory-based
Assimilators”. Journal of Cross-cultural Psychology, vol. 29, no. 5, 1998, h. 630-655. 4S. Mennell & J. Rundell, “Introduction: Civilization, Culture and the Human Self-
image”. In Classical Readings on Culture and Civilization, (Routledge, 2017), h. 9-44.; J. P.
Arnason, “Civilization, Culture and Power: Reflections on Norbert Elias' Genealogy of the
West”. Thesis Eleven, vol. 24, no. 1, 1989, h. 44-70. 5Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), h.
146.
32
merumuskan hukum. Ada salah satu kaidah ushul yang berbunyi: “al-„adah
muhakkamah” yang menunjukkan bahwa „urf itu punya posisi penting.6
Agama (Islam) dan budaya (lokal) masing-masing memiliki simbol-simbol dan
nilai tersendiri. Islam adalah simbol yang melambangkan ketaatan kepada Allah.
Kebudayaan (lokal) juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup
didalamnya dengan ciri khas kelokalannya. Agama memerlukan sistem simbol, atau
dengan kata lain memerlukan kebudayaan agama, namun keduanya berbeda. Agama
adalah sesuatu yang final, universal dan absolut, sedangkan kebudayaan bersifat
particular, relative dan temporer. Meski demikian, dialektika di antara keduanya
adalah sebuah keniscayaan. Islam memberikan warna dan spirit pada kebudayaan
setempat, sedangkan kebudayaan lokal memberi kekayaan kepada Islam.7
Manusia dalam pandangan Islam diposisikan sebagai khalifah (wakil Allah) di
bumi (QS. al-Baqarah [2]: 30). Tugas manusia sebagai khalifah disempurnakan
dengan tugas „ubudiyyah-nya sebagai hamba Allah. Sebagai khalifah Allah,
manusia harus berperan aktif di dunia, dan memiliki kewajiban memakmurkan
bumi, mengelolanya demi kemaslahatan bersama, memelihara keharmonisan
dengan lingkungan alam dan menebar kebaikan di alam semesta. Manusia harus
memelihara alam dengan penuh kasih sayang, mampu menjaga keharmonisan
terhadap, litosfir, atmosfir, tanah, mineral, energi serta air. Dalam menjalani
perannya di muka bumi, manusia harus selalu menyadari akan tanggung jawabnya
sebagai khalifah. Sehingga sekalipun manusia sudah mampu mencapai kebudayaan
yang tinggi, manusia tetap tidak akan semena-mena mengeksploitasi alam.
Beberapa ahli berusaha merumuskan berbagai definisi tentang kebudayaan.
Koetjaraningrat mengatakan kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan,
tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan sosial yang didapat melalui
proses belajar. Koentjaraningrat lebih lanjut mengatakan kebudayaan memiliki
unsur-unsur yang bersifat universalditemukan di semua kebudayaan bangsa-
bangsa di duniaada bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem
peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi dan
kesenian.8 Ini berarti bahwa seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan. Hampir
seluruh tindakan manusia dalam masyarakat dibiasakan melalui proses belajar
6T. M. Salisu, “„Urf/„Adah (Custom): An Ancillary Mechanism in Shari „ah”. Ilorin
Journal of Religious Studies, vol. 3, no. 2, 2013, h. 133-148.; A. Shabana, “'Urf and'Adah
within the Framework of Al-Shatibi's Legal Methodology”. UCLA J. Islamic & Near
EL, vol. 6, 2006, h. 87.; A. Rachim, “Al Adah Muhakkamah”. Al-Mawarid Journal of
Islamic Law, vol. 4, 1995, h. 8-13. 7S. Bin Zayyad & B. R. Sinclair, “Culture, Context+ Environmental Design:
Reconsidering Vernacular in Modern Islamic Urbanism”. Architectural Research:
Addressing Societal Challenges, vol. 1, 2017, h. 535-542.; H. Al-Aoufi, N. Al-Zyoud, & N.
Shahminan, “Islam and the cultural conceptualisation of disability”. International Journal of
Adolescence and Youth, vol. 17, no. 4, 2012, h. 205-219.; B. Larkin, B. Meyer, & E. K.
Akyeampong, “Pentecostalism, Islam & Culture”. Themes in West Africa's History, 2006, h.
286-312. 8Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi …, h. 165.
33
sebagaimana beberapa ahli antropologi seperti Wissler,9 Kluckhohn,
10 Davis dan
Hoebel11
mengatakan kebudayaan dan tindakan kebudayaan adalah segala tindakan
yang harus dibiasakan oleh manusia melalui belajar. Hanya sedikit yang tidak perlu
dibiasakan melalui belajar, yaitu beberapa tindakan naluri, beberapa tindakan
refleks dan beberapa tindakan membabi buta.
Lebih lanjut Koentjaraningrat membagi kebudayaan menjadi tiga wujud, yaitu:
1. Wujud kebudayaan yang berupa ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan
sebagainya. Kebudayaan ini bersifat abstrak, tidak dapat diraba atau difoto.
Letaknya didalam kepala atau alam pikiran warga masyarakat.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu aktifitas serta Tindakan berpola dari
manusia itu sendiri, atau biasa juga disebut sistem sosial. Sistem sosial ini
terdiri dari aktifitas-aktifitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, dan
bergaul satu sama lain dari detik ke detik, dari hari ke hari, dan dari tahun
ke tahun, menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan.
Wujud yang kedua ini bersifat kongkrit, dapat diobservasi, difoto dan
didokumentasi.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud ketiga
ini disebut juga kebudayaan fisik. Benda fisik ini merupakan hasil ide-ide
atau pikiran-pikiran dan Tindakan manusia.12
Geertz melangkah lebih komprehensif mengatakan kebudayaan adalah
keseluruhan pengetahuan, kepercayaan dan nilai-nilai yang dimilki manusia sebagai
makhluk sosial. Sistem gagasan itu kemudian melahirkan simbol-simbol yang
ditransmisikan secara historis. Masyarakat kemudian menggunakan model
pengetahuan ini untuk berkomunikasi, bersikap dan bertindak dalam rangka
memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebudayaan adalah sistem pemaknaan yang
dimilki bersama dan kebudayaan merupakan hasil dari proses sosial dan bukan
proses perorangan. Geertz kemudian menyarankan agar dalam memahami suatu
kebudayaan juga harus memerhatikan maknanya, jangan hanya fokus pada tingkah
laku ataupun hubungan sebab-akibat.13
Seorang ahli antropologi harus mampu
menafsirkan simbol-simbol agar dapat memahami makna dari sebuah kebudayaan.
Berangkat dari pendapat Geertz, Purwanto mengatakan pemahaman kebudayaan
9S. A. Freed & R. S. Freed, “Clark Wissler and the Development of Anthropology in
the United States”. American Anthropologist, vol. 85, no. 4, 1983, h. 800-825. 10
R. Boroch, “A Formal Concept of Culture in the Classification of Alfred L. Kroeber
and Clyde Kluckhohn”. Analecta, vol. 25, no. 2, 2016. 11
E. A. Hoebel, “Anthropology in Education”. Yearbook of Anthropology, 1955, h.
391-395.; Lihat juga E. A. Hoebel, “Karl Llewellyn: Anthropological Jurisprude”. Rutgers
Law Review, vol. 18, 1963, h. 735.; E. A. Hoebel, Man in the Primitive World: An
introduction to Anthropology, vol. 1, (New York: Toronto: McGraw-Hill Book Company,
1949). 12
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi…,h. 150-152. 13
C. Geertz, The Interpretation Cultures, (New York: Basic Books Inc. Publisher,
1973), h. 89.
34
juga meliputi bagaimana warga masyarakat melihat, merasakan dan berfikir
mengenai sesuatu di sekelilingnya.14
Pendapat para ahli sebelumnya tidak jauh berbeda dengan Tumanggor yang
mengatakan kebudayaan adalah konsep, keyakinan, nilai dan norma yang dianut
masyarakatikut memengaruhi perilakunya dalam menghadapai tantangan
kehidupan di sekitarnya.15
Kebudayaan itu tidak dibawa dari lahir, namun diperoleh
dari proses belajar sebagaimana Tumanggor lebih spesifik mengatakan kebudayaan
lahir dalam kehidupan masyarakat melalui tiga perwujudan, yakni wujud
kebudayaan sebagai sistem gagasan, wujud kebudayaan sebagai aktifitas sosial dan
wujud kebudayaan yang melahirkan materi budaya, baik yang melekat dalam jiwa
atau pikiran ataupun materi yang ada di kebendaan (artefak).16
Upaya pendefinisian konsep kebudayaan juga diutarakan Tylor bahwa
kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum,
adat serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai
bagian dari anggota masyarakat.17
Sejak 1950-an, ahli antropologi seperti Kroeber
dan Kluckhohn mencoba merumuskan kembali kosep kebudayaan secara lebih
sistematik dalam bukunya Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions
(1952). Mereka berpendapat bahwa kebudayaan adalah keseluruhan pola tingkah
laku manusia, baik eksplisit maupun implisit yang diperoleh dan diturunkan melalui
simbol, yang akhirnya mampu membentuk sesuatu yang khas dari kelompok-
kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam benda-benda materi. Dalam hal
ini, struktur sosial hanya dianggap sebagai salah satu segi dari masyarakat.
Kluckhohn juga mengatakan bahwa ada unsur-unsur kebudayaan yang sifatnya
universal dalam setiap kebudayaan manusia; meliputi sistem organisasi sosial,
sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem pengetahuan, kesenian dan religi.
Lebih lanjut dikatakan bahwa setiap unsur kebudayaan pada hakikatnya
mengandung tiga wujud kebudayaan, yaitu sistem budaya, sistem sosial dan artefak.
Sementara itu, pada setiap unsur-unsur kebudayaan juga menjelma wujud dari
kebudayaan, baik sebagai sistem budaya, sistem sosial maupun artefak.18
Secara spesifik Yuanzhi membagi budaya dalam dua pengertian, yakni
pengertian sempit dan pengertian luas. Budaya dalam pengertian sempit mengacu
kepada semua hasil kegiatan dan akal budi manusia seperti sastra, seni, pendidikan,
kepercayaan, adat istiadat, dan sebagainya. Sementara budaya dalam pengertian
14
Hari Purwanto, Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 58-59. 15
Rusmin Tumanggor dkk, Ilmu Sosial & Budaya Dasar, (Jakarta: Kencana, 2010), h.
141. 16
Tumanggor dkk., Ilmu Sosial & Budaya…, h. 23-25. 17
E. B. Taylor, Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology,
Philosophy, Religion, Art, and Custom, vol. 2, (London: John Murray, Albemarle Street,
1871), h. 401. Lihat juga T. Larsen, “EB Tylor, Religion and Anthropology”. The British
Journal for the History of Science, 2013, h. 467-485.; L. Ratnapalan, “EB Tylor and the
Problem of Primitive Culture”. History and Anthropology, vol. 19, no. 2, 2008, h. 131-142. 18
A. L. Kroeber & C. Kluckhohn, “Culture: A Critical Review of Concepts and
Definitions”. Papers: Peabody Museum of Archaeology & Ethnology, Harvard University,
vol. 47, no. 1, 1952, h. viii.
35
luas berarti keseluruhan pengetahuan dan kreasi manusia, baik yang bersifat materi
maupun non materi.19
Artinya, sifat budaya itu saling memengaruhi, atau budaya
antar bangsa itu bersifat timbal balik. Suatu bangsa memengaruhi bangsa lain
sekaligus menerima pengaruh dari bangsa lain, dan itu yang terjadi pada budaya
Tionghoa dan Indonesia.20
Linton membagi kebudayaan menjadi dua, yakni budaya yang nampak (overt
culture) dan bagian yang tidak nampak (covert culture).21
Hoenigman sebagaimana
dikutip Barzilai mengatakan wujud kebudayaan yang tidak nampak (covert culture)
adalah ide atau gagasan, sesuatu yang abstrak yang berbeda dengan overt culture.
Namun, overt culture juga merupakan bagian dari sistem budaya, karena sistem
budaya tidak hanya gagasan-gagasan tetapi mencakup sistem nilai budaya, konsep-
konsep, tema-tema pikir dan keyakinan.22
Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Budaya ada karena adanya manusia, atau dengan kata lain, pendukung
kebudayaan adalah manusia itu sendiri. Budaya tidak akan mati sekalipun
manusianya mati, karena kebudayaan yang ada akan diwariskan kepada
keturunannya dan seterusnya. Pewarisan kebudayaan tidak selalu bersifat vertikal
tetapi bisa juga horizontal, yaitu manusia yang satu belajar kebudayaan dari
manusia lainnya.23
Setiap pengalaman yang dialami manusia, akan diteruskan dan
dikomunikasikan kepada generasi berikutnya oleh individu lain.
Kebudayaan itu bukan sesuatu yang statis dan kaku, tetapi senantiasa berubah
sesuai dengan perubahan sosial yang ada. Suatu budaya dalam masyarakat akan
terus mengalami perubahan termasuk tradisi, dan biasanya, perubahan budaya itu
terjadi karena adanya kontak komunikasi atau dialog melalui bahasa. Tanpa bahasa,
proses pengalihan kebudayaan tidak akan terjadi. Dialog meniscayakan adanya
persamaan dan kesamaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Anggapan bahwa
kebudayaan tertentu lebih tinggi dari kebudayaan lain hanya akan melahirkan
fasisme, nativisme dan chauvinisme. Dengan dialog diharapkan ada ide baru yang
19
Kong Yuanzhi, Silang Budaya Tiongkok Indonesia, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu
Populer, 2005), h. xviii. 20
H. Kurniawan, “The Role of Chinese in Coming of Islam to Indonesia: Teaching
Materials Development Based on Multiculturalism”. Paramita: Historical Studies
Journal, vol. 27, no. 2, 2017, h. 238-248. 21
R. Linton, The Study of Man: An Introduction, (Appleton-Century, 1936). 22
G. Barzilai, Communities and Law: Politics and Cultures of Legal Identities,
(University of Michigan Press, 2003), h. 109. 23
D. Nettle, “Selection, Adaptation, Inheritance and Design in Human Culture: The
view from the Price Equation”. Philosophical Transactions of the Royal Society, vol. 375,
no. 1797, 2020, h. 20190358.; R. Wang, “Inheritance of Intangible Cultural Heritage of
Oroqen Ethnic Group Based on Computer Network Culture”. In Journal of Physics:
Conference Series, vol. 1574, no. 1, (IOP Publishing, 2020), h. 012003.; W. Su, “Study on
the Inheritance and Cultural Creation of Manchu Qipao Culture”. In 3rd International
Conference on Art Studies: Science, Experience, Education (ICASSEE 2019), (Atlantis
Press, 2019).
36
bisa memperkaya kebudayaan, dan di samping untuk memperkaya kebudayaan,
dialog juga bertujuan untuk mencari titik temu antar kebudayaan yang ada.24
Budaya dalam perkembangannya akan terus mengalami perubahan, tidak
bersifat konstan. Perubahan budaya bisa saja terjadi karena pertemuan dua atau
lebih budaya. Koentjaraningrat dalam konteks ini mengatakan perubahan
kebudayaan bisa terjadi melalui lima proses, yaitu: 1) Proses belajar terhadap
kebudayaan itu sendiri yang meliputi proses internalisasi, proses sosialisasi dan
proses enkulturasi. Proses enkulturasi adalah proses penyesuaian pikiran, sikap
terhadap adat, sistem norma dan dan peraturan yang ada dalam suatu kebudayaan.
2) Proses evolusi, yaitu perubahan budaya yang terjadi secara berulang namun
dalam rentang waktu yang panjang. 3) Proses diffusi, yaitu perubahan budaya yang
terjadi karena migrasi yang dilakukan oleh kelompok manusia yang membawa
unsur kebudayaannya. 4) Proses inovasi, yaitu perubahan budaya yang terjadi
karena adanya penemuan baru dalam kebudayaan, misal teknologi. 5) Proses
akulturasi dan asimilasi yaitu perubahan sosial yang terjadi karena adanya
percampuran unsur budaya asing terhadap budaya setempat.25
Kebudayaan pada dasarnya memuat beragam corak, yakni bisa bentuknya tetap
atau sulit berubah, kebudayaan yang dipengaruhi unsur kebudayaan asing (covert
culture)26
serta kebudayaan yang lentur dengan perkembangan jaman sehingga
mudah beradaptasi dengan unsur-unsur kebudayaan asing (overt culture).27
Beberapa contoh covert culture adalah keyakinan keagamaan yang dianggap suci,
beberapa adat yang sudah dipelajari dan diamalkan sejak kecil, dan sistem nilai-
nilai budaya. Sementara yang termasuk overt culture adalah kebudayaan fisik
seperti alat teknologi dan benda-benda yang berguna bagi kehidupan sehari-hari,
serta gaya hidup dan ilmu pengetahuan.28
Seiring perkembangannya, kebudayaan mengalami perubahan begitu cepat,
dan para antropolog tidak dapat meneliti masyarakat seperti itu tanpa mempelajari
keadaaan sebelumnya. Sementara sebuah kebudayaan akan dipahami secara
komprehensif jika dipahami juga konteks masa lalunya. Karena anggapan seperti
itu, maka pendekatan historis diperlukan. Para ahli antropologi dari Amerika Latin
banyak yang menggunakan data historis dalam penelitiannya. Data historis ini
24
Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016), h.
xiii. 25
Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, (Jakarta: Dian Rakyat, 1977),
h. 142. 26
L. E. Brown, “Cold War, Culture Wars, War on Terror: the NEA and the art of public
diplomacy”. Cold War History, 2020, h. 1-19.; T. Schmader, H. B. Bergsieker, & W. M.
Hall, “Cracking the Culture Code”. In Applications of Social Psychology by J. Forgas, K.
Fiedler & W. Crano (ed.), (New York: Routledge, 2020), h. 334-355. 27
R. Busbridge, B. Moffitt & J. Thorburn, “Cultural Marxism: Far-right Conspiracy
Theory in Australia‟s Culture Wars”. Social Identities, 2020, h. 1-17.; R. K. Lawrence, M.
Edwards, G. W. Chan, J. A. Cox, & S. C. Goodhew, “Does Cultural Background Predict the
Spatial Distribution of Attention?. Culture and Brain, 2019, h. 1-29. 28
L. Qian & M. Garner, “A Literature Survey of Conceptions of the Role of Culture in
Foreign Language Education in China (1980–2014)”. Intercultural Education, vol. 30, no. 2,
2019, h. 159-179.
37
dipakai jika diperlukan, bukan untuk menonjolkan permasalahannya sebagaimana
juga Herskovits menggunakan data sejarah dalam penelitiannya di kalangan orang
Negro.29
Boas (1858-1942) adalah salah seorang pelopor aliran historisme Amerika,
bahkan akhirnya dianggap sebagai bapak antropologi Amerika. Boas berpendapat
bahwa sejarah dapat dijadikan alat untuk memahami kebudayaan yang tersebar di
muka bumi. Perhatian Boas terhadap analisis spesifik dari cultural history agaknya
sangat dipengaruhi oleh dua tradisi ilmu pengetahuan di luar paham evolusionis
yang berkembang di Amerika pada waktu itu, yaitu pendekatan geografi dan
pendekatan field work. Boas berpendapat bahwa berbagai peristiwa unik dan
spesifik yang pernah terjadi dalam sejarah akan dapat dipakai untuk menjelaskan
fenomena kebudayaan di masa sekarang. Menurutnya, kehidupan yang nampak
sekarang yang terjadi pada suatu masyarakat adalah akibat dari peristiwa masa lalu.
Peristiwa-peristiwa yang yang terjadi dalam kehidupan suatu bangsa juga
dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar masyarakat tersebut.30
Persoalan mengenai proses perubahan kebudayaan dalam dunia antropolgi
merupakan suatu persoalan pokok bahkan sejak zaman lahirnya ilmu ini. Awalnya
perubahan kebudayaan dianggap sebagai akibat adanya suatu kekuatan yang
terdapat di dalam inti dari tiap-tiap kebudayaan di dunia. Kekuatan yang dimaksud
di dalam tiap-tiap kebudayaan adalah kekuatan evolusi. Di samping itu, timbul juga
anggapan bahwa proses perubahan kebudayaan itu adalah akibat dari adanya gerak
persebaran dan perpaduan kembali dari kebudayaan-kebudayaan yang ada, dikenal
dengan istilah “difusi”.
Penyelidikan yang mengkhususkan terhadap proses-proses yang terjadi apabila
dua kebudayaan bertemu atau akulturasi terjadi pada perkembangan selanjutnya.
Menurut Koentjaraningrat karangan-karangan yang bersifat teoritis sudah ada sejak
tahun 1910 namun belum mempunyai dasar yang kuat. Misalnya, karangan G. Sergi
(1911)31
tentang pengaruh yang berbeda-beda kekuatannya dari suatu kebudayaan
asing pada berbagai adat-istiadat dalam suatu kebudayaan asli, karangan Triggs
(1912)32
tentang runtuhnya kebudayaan asli yang kena pengaruh kebudayaan asing,
kemudian karangan Marett (1918)33
tentang alam pikiran suatu bangsa asli yang
kena pengaruh kebudayaan asing.34
29
M. J. Herkovits, Acculturation: The Study of Culture Contact, (New York: Peter
Smith, 1958). 30
F. Boas, “History and Science in Anthropology: A Reply”. American Anthropologist,
vol. 38, no. 1, 1936, h. 137-141. 31
G. Sergi, L'uomo secondo le origini, l'antichità, le variazioni e la distribuzione
geografica. Sistema naturale di classificazione. Con 212 figure nel testo, 107 tavole
separate e una carta geografica dei generi umani, (Fratelli Bocca, 1911). 32
O. L. Triggs, “The Decay of Aboriginal Races (Illustrated)”. The Open Court, no.
10, 1912. 33
R. R. Marett, “Presidential Address. The Transvaluation of Culture”. Folklore, vol.
29, no. 1, 1918, h. 15-33. 34
Koentjaraningrat, Metode-Metode Antropologi dalam Penyelidikan-Penyelidikan
Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1958), h. 442.
38
Lembong berpendapat bahwa membangun sebuah bangsa harus dimulai dari
membangun kebudayaannya, begitupun membangun Indonesia harus dimulai dari
jantung kebudayaan yaitu manusianya. Selama ini semua orang hanya fokus pada
pembangunan fisik dan mengabaikan “pembangunan” manusianya. Lembong
melalui idenya yang dikenal dengan istilah “penyerbukan silang antarbudaya”
(cross culture fertilization) berupaya membangun manusia Indonesia agar dapat
mengembangkan potensi yang dimiliki.35
Manusia Indonesia harus mampu
melakukan penyerbukan silang antar budaya-budaya unggul yang ada, juga budaya-
budaya unggul yang berada dari luar, atau budaya asing. Menurutnya, tiap-tiap
daerah atau bangsa memiliki unsur-unsur kebaikan dan keunggulan termasuk etnis
Tionghoa, yang apabila dipadukan akan menghasilkan sebuah “budaya Indonesia
baru” yang unggul. Budaya Indonesia harus mampu menjadikan manusia Indonesia
mampu mengambil budaya luhur yang ditemui serta kemudian
mengembangkannya.
Dengan jalan penyerbukan silang antar budaya, etos kerja yang bagus, yang
dimiliki sebuah kelompok bisa diterapkan di kelompok lain dan melahirkan budaya
baru, yakni etos kerja dalam bingkai budaya Indonesia. Jadi, dalam penyerbukan
silang antarbudaya, kita tidak hanya mengakui adanya kemajemukan yang ada di
Indonesia, namun juga mengakui bahwa setiap daerah atau kelompok memiliki
kebaikan-kebaikan dan keunggulan yang kalau keunggulan-keunggulan itu
dipadukan akan menghasilkan budaya Indonesia baru yang unggul yang mampu
berdiri tegak dan bersaing kompetitif dengan semua budaya bangsa dalam bingkai
peradaban dunia. Dalam konteks ini, penyerbukan silang antarbudaya adalah sebuah
bentuk strategi kebudayaan baru untuk memajukan Indonesia.36
1. Akulturasi
Akulturasi adalah proses di mana kontak antara kelompok budaya yang
berbeda mengarah pada perolehan pola budaya baru oleh satu kelompok, atau
mungkin kedua kelompok, dengan adopsi semua atau sebagian budaya yang lain.
Pendefinisian tersebut sebagaimana dalam Dictionary of Sociology, dijelaskan
bahwa “Acculturation is a process in which contacts between different cultural
groups lead to the acquisition of new cultural patterns by one group, or perhaps both
groups, with the adoption of all or parts of the others‟s culture”.37
Sementara
Redfield, Linton dan Herskovits adalah yang pertama kali memberikan definisi
secara sistematik tentang akulturasi. Mereka mengatakan akulturasi akan terjadi
ketika kelompok individu yang memiliki budaya berbeda bersentuhan langsung dan
akan mengakibatkan perubahan dalam pola budaya asli dari salah satu atau kedua
35
A. Rukmana dan E. Lembong (ed.), Penyerbukan Sialng Antarbudaya: Membangun
Manusia Indonesia, (Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Kompatindo, Jakarta, 2015). 36
J. Oetama dan A. S. Maarif, Penyerbukan Silang Antar Budaya: Membangun
Manusia Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 2015), h. xii-xxvi. 37
David Jary dan Julia Jary, HarperCollins Dictionary of Sociology, (New York:
HarperPerennial, 1991), h. 3.
39
kelompok tersebut.38
Namun, definisi tersebut dalam perkembangannya mendapat
banyak kritikan dari para antropolog kemudian, karena ada beberapa poin yang sulit
ditafsirkan. Misalnya, perbedaan antara akulturasi dan asimilasi, akulturasi itu suatu
proses ataukah menunjukkan suatu keadaan?. Sekalipun terdapat kesulitan,
keduanya masuk dalam ruang lingkup studi perubahan kebudayaan.
Thurnwarld mengatakan “acculturation is a process, not an isolated event”.39
Dalam konteks ini Thurnwarld lebih menekankan pada proses yang terjadi di
tingkat individual karena suatu proses adaptasi terhadap kondisi kehidupan baru
itulah yang disebut dengan akulturasi. Dalam konteks ini Koentjaraningrat
mengatakan akulturasi juga bisa digunakan untuk membahas berbagai hal yang
berkaitan dengan penyesuaian individu terhadap suatu budaya baru. Contohnya
dalam sejarah kebudayaan manusiabanyak yang melakukan migrasi yaitu gerak
perpindahan suku bangsa dari suatu tempat ke tempat lain yang menyebabkan
bertemunya antar kelompok manusia dengan kebudayaan berbeda, dan sebagai
akibatnya, individu-individu itu dihadapkan pada kebudayaan asing.40
Akulturasi itu sendiri sebagaimana dikemukakan Koentjaraningrat merupakan
proses sosial yang terjadi bila mana dalam suatu masyarakat dengan suatu
kebudayaan tertentu, dipengaruhi unsur kebudayaan asing yang berbeda sifatnya.
Unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diakomodasi dan diintegrasikan ke
dalam kebudayaan sendiri tanpa kehilangan kepribadian kebudayaan sendiri.41
Jalan
yang dilalui akulturasi sebagaimana Soekanto mengatakan bisa dibedakan antara
penyesuaian dari lembaga-lembaga kemasyarakatan dan penyesuaian dari individu
yang ada dalam masyarakat. Meskipun ia sendiri menyatakan bahwa lembagalah
yang mendapat penilaian tertinggi menjadi saluran utama.42
Jadi, akulturasi pada
dasarnya merupakan fenomena yang dihasilkan sejak kedua kelompok atau individu
berbeda kebudayaan mulai melakukan kontak langsung, yang diikuti perubahan
pola kebudayaan asli dari salah satu atau kedua kelompok tersebut. Jika ada dua
masyarakat atau lebih menjalin kontak sosial dalam waktu yang cukup lama, maka
cepat atau lambat kebudayaan dari masing-masing pihak yang bersangkutan tentu
akan saling berkenalan dan saling memengaruhi. Akibat, kontak kebudayaan
tersebut menimbulkan proses akulturasi. Proses akulturasi di antaranya dapat terjadi
antara aspek material dan non-material dari kebudayaan yang sederhana dengan
kebudayaan yang kompleks, dan antara kebudayaan yang kompleks dengan
kebudayaan yang kompleks pula.43
Sementara Saebani mengatakan akulturasi meliputi fenomena yang timbul
sebagai hasil percampuran kebudayaan jika berbagai kelompok manusia dengan
38
R. Redfield, R. Linton, & M. J. Herskovits, “Memorandum for the Study of
Acculturation”. American Anthropologist, vol. 38, no. 1, 1936, h. 149-152. 39
R. Thurnwald, “The Psychology of Acculturation”. American Anthropologist, vol. 34,
no. 4, 1932, h. 557-569. 40
Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta: Djembatan,
1990), h. 248. 41
Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan…, h. 91. 42
S. Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h.
367-368. 43
B. A. Saebani, Pengantar Antropolog, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 191.
40
kebudayaan yang beragam bertemu mengadakan kontak secara langsung dan terus
menerus, kemudian menimbulkan perubahan dalam pola-pola kebudayaan yang
original dari salah satu kelompok atau pada keduanya.44
Suyono dalam Kamus Antropologi mengatakan akulturasi merupakan
pengambilan atau penerimaan satu atau beberapa unsur kebudayaan yang berasal
dari pertemuan dua atau beberapa kebudayaan yang saling berhubungan atau
bertemu.45
Sementara Lauer mendefinisikan akulturasi sebagai proses sosial yang
dimulai sejak kedua kelompok atau individu yang berbeda kebudayaan mulai
melakukan kontak langsung, yang diikuti perubahan pola kebudayaan asli dari salah
satu kelompok atau keduanya.46
Berbeda dengan Joyomartono yang masih bersifat
“ragu-ragu” mengatakan bahwa dalam akulturasi bisa jadi hanya salah satu dari dua
kebudayaan yang berubah, namun bisa juga terjadi perubahan pada kedua
kebudayaan. Dari pengertian tersebut, akulturasi memiliki makna yang berbeda
dengan difusi. Suatu kebudayaan dapat mengambil anasir kebudayaan lain tanpa
terjadinya akulturasi.47
Pendapat Koetjaraningrat di atas senada dengan Keesing mengatakan
akulturasi sebagai suatu proses sosial yang timbul jika suatu kelompok manusia
dengan budaya-budaya tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur budaya asing
tertentu, sehingga kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah
kedalam kebudayaan sendiri, tetapi tanpa menyebabkan identitas kebudayaan
sendiri hilang.48
Pengertian yang sama juga dikemukakan Haviland bahwa
akulturasi adalah proses sosial yang terjadi jika dua kebudayaan atau lebih bertemu
dalam jangka waktu yang lama dan mengakibatkan perubahan-perubahan besar.49
Menurut Berry akulturasi merupakan proses perubahan budaya dan psikologis
yang terjadi sebagai akibat pertemuan dua atau lebih budaya dan anggota masing-
masing kelompok etnik. Akulturasi mengakibatkan perubahan budaya dan
psikologis karena adanya kontak dengan budaya lain. Perilaku seseorang cenderung
berubah setelah mengalami perjumpaan dengan budaya lain. Misalnya, ketika
Inggris menduduki India dan Afrika, maka banyak di antara orang India ataupun
Afrika yang terakulturasi ke dalam gaya hidup orang Inggris, juga banyak di antara
mereka yang berubah perilakunya, baik dari segi bahasa, agama, pakaian dan
lainnya.50
Di negara-negara Eropa yang memiliki banyak daerah jajahan atau di negeri
Amerika Serikat yang di dalam wilayahnya mempunyai penduduk dari suku-suku
bangsa Indianbanyak timbul perubahan masyarakat dan kebudayaan yang
44
Saebani, Pengantar Antropolog... h. 189. 45
A. Suyono, Kamus Antropologi, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 15. 46
R. H. Lauer, Perspektif tentang Perubahan Sosial, terj., (Jakarta: Rineka Cipta,
1993), h. 403. 47
M. Joyomartono, Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat dalam Pembangunan,
(Semarang: IKIP Semarang Press, 1991), h. 41. 48
F. M. Keesing, Culture Change: An Analysis and Bibliography of Anthropological
Sources to 1952, no. 1. (New York: Octagon Books, 1973). 49
W. A. Haviland, Cultural Anthropology, (Wadsworth Publishing Company, 2002). 50
J. W. Berry, “Globalisation and Acculturation”. International Journal of Intercultural
Relations, vol. 32, no. 4, 2008, h. 328-336.
41
merupakan perpaduan dari beberapa kebudayaan. Di Inggris, studi semacam ini
disebut culture contact, sedangkan di Amerika lebih banyak digunakan istilah
acculturation.51
Menurut Puspito akulturasi dapat didefinisikan sebagai proses
sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu
dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian
rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke
dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan
itu sendiri.52
Senada dengan Puspito, Supatmo mengatakan akulturasi adalah
perubahan budaya yang terjadi jika dua kebudayaan atau lebih bertemu, kemudian
kebudayaan asing itu secara bertahap diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri
tanpa mengakibatkan hilangnya karakter atau identitas budaya itu. Lebih jauh
Supatmo mengatakan bahwa proses perubahan budaya yang terjadi tidak selamanya
kelompok kebudayaan setempat yang bersifat pasif dan kelompok budaya asing
yang aktif, tetapi bisa juga terjadi di antara mereka tindakan saling menerima dan
memengaruhi.53
Haviland mengatakan akulturasi bisa terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu: 1)
Substitusi. Bentuk substitusi adalah proses penggantian unsur kebudayaan lama
diganti dengan unsur kebudayaan baru yang lebih memberikan nilai bagi kehidupan
masyarakat. Misalnya, binatang kerbau yang digunakan untuk membajak sawah
diganti dengan mesin tractor. 2) Sinkretisme. Bentuk sinkretisme adalah proses
meleburnya budaya lama dengan unsur budaya baru sehingga tercipta kebudayaan
baru. Misalnya, bercampurnya unsur-unsur ajaran agama Hindu-Buddha dengan
ajaran Islam sehingga menghasilkan sistem kepercayaan Islam Kejawen. 3) Adisi
(addition). Unsur budaya yang lama yang masih berfungsi ditambah unsur baru
sehingga memberikan nilai lebih. Misalnya, beroperasinya kendaraan bermotor
untuk melengkapi alat transportasi tradisional seperti dokar, becak dan lain-lain. 4)
Dekulturasi (deculturation). Bentuk ini adalah proses hilangnya atau tidak
berfungsinya unsur-unsur kebudayaan lama digantikan dengan unsur kebudayaan
baru, sebagai contoh, mesin penggilingan padi yang sudah menggantikan
penggunaan lesung dan gebugan untuk menumbuk padi. 5) Originasi. Bentuk
originasi adalah proses masuknya unsur budaya baru yang sebelumnya tidak dikenal
sama sekali sehingga menimbulkan perubahan sosial dalam masyarakat. Misal,
masuknya teknologi listrik ke pedesaan telah menyebabkan perubahan besar dalam
berbagai aspek kehidupan masyarakat desa. Informasi yang diterima masyarakat
telah menimbulkan perubahan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan,
perekonomian, gaya hidup, tingkah laku dan hiburan. 6) Penolakan (rejection).
Masyarakat yang tidak siap dan tidak setuju dengan proses percampuran cenderung
melakukan penolakan sebagaimana kerab dijumpai masih ada di antara masyarakat
51
Hari Poerwanto, “Asimilasi, Akulturasi, dan Integrasi Nasional”. Humaniora, vol. 11,
no. 3, 1999, h. 29-37. 52
Hendro Puspito, Sosiologi Semantik, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 233. 53
Supatmo, “Keragaman Seni Hias Bangunan Bersejarah Masjid Agung Demak”.
Imajinasi, vol. 10, 2, 2016, h. 107–120.
42
yang tidak mau berobat ke dokter jika sakit dan lebih memilih berobat ke kyai atau
dukun.54
Rohmanu dalam penelitiannya tentang pernikahan masyarakat etnik Jawa di
Selangor, Malaysia mendapati tradisi pernikahan yang dilakukan masyarakat Jawa
di Selangor masih mempertahankan tradisi-tradisi Jawa meskipun mereka sudah
lama beradaptasi dengan budaya Melayu sebagai tempat kelahirannya. Menurutnya
akulturasi yang terjadi mengarah pada substitusi dan sinkretisme. Substitusi dalam
arti bahwa ada beberapa tradisi Jawa yang diganti dengan budaya Melayu karena
dianggap memiliki substansi yang sama. Adapun yang dimaksud sinkretisme adalah
bahwa dua budaya itu melebur menjadi sebuah budaya baru yang sifatnya khas.55
Akulturasi juga menunjuk pada terjadinya perubahan yang dialami oleh
seseorang akibat kontak dengan budaya lainnya, sekaligus juga akibat keikutsertaan
dalam proses akulturasi yang memungkinkan budaya dan kelompok etnis
menyesuaikan diri dengan budaya yang lainnya. Akulturasi biasanya terjadi pada
seorang pendatang yang perlu menyesuaikan diri dengan budaya yang baru
ditemuinya. Perubahan budaya yang terjadi pada individu menunjuk pada sikap,
nilai, dan jati diri. Dalam kondisi seperti ini, kesiapan mental dan pendidikan
seseorang sangat menentukan dalam beradapatasi dengan budaya yang baru.56
Usman membagi proses akulturasi menjadi dua bentuk,57
yaitu: pertama,
akulturasi damai (penetration pasifique). Akulturasi ini terjadi jika masyarakat
penerima kebudayaan menerima unsur-unsur kebudayaan asing secara damai tanpa
paksaan. Misalnya, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia.
Kedua macam kebudayaan tersebut diterima masyarakat pribumi secara damai
tanpa konflik, tetapi memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. Pengaruh
kedua kebudayaan itupun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya
masyarakat. Kedua, akulturasi ekstrim (penetration violante). Akulturasi jenis ini
terjadi dengan cara merusak, memaksa lewat kekerasan, perang, dan penaklukkan.
Akibatnya, masyarakat yang dikalahkan dipaksakan untuk menerima unsur-unsur
kebudayaan asing dari pihak yang menang. Contohnya, masuknya kebudayaan
Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga
menimbulkan goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat.
54
W. A. Haviland, Antropologi, terj. R. G. Soekadijo, (Jakarta: Erlangga, 1988), h. 263. 55
A. Rohmanu, “Acculturation of Javanese and Malay Islam in Wedding Tradition of
Javanese Ethnic Community at Selangor, Malaysia”. KARSA: Journal of Social and Islamic
Culture, vol. 24, no. 1, 2016, h. 52-66. 56
J. Cullum & H. C. Harton, “Cultural evolution: Interpersonal Influence, Issue
Importance, and the Development of Shared Attitudes in College Residence
Halls”. Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 33, no. 10, 2007, h. 1327-1339.; J.
W. Berry, U. Kim, S. Power, M. Young, & M. Bujaki, “Acculturation Attitudes in Plural
Societies”. Applied Psychology, vol. 38, no. 2, 1989, h. 185-206.; T. P. Hannigan, “Traits,
Attitudes, and Skills that are Related to Intercultural Effectiveness and their Implications for
Cross-cultural Training: A Review of the Literature”. International Journal of Intercultural
Relations, vol. 14, no. 1, 1990, h. 89-111. 57
A. R. Usman, Etnis Cina Perantauan di Aceh, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2009), h. 45-47.
43
Dari sekian perdebatan, memang para antropolog mendefinisikan akulturasi
secara berbeda, tetapi semua sepakat bahwa konsep itu berkaitan dengan proses
sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan kebudayaannya bertemu
dengan kelompok manusia yang lain kemudian terjadi proses saling memengaruhi
hingga terjadi perubahan pada kebudayaan asli suatu kelompok atau pada
keduanya.58
Powell adalah orang yang pertama kali memperkenalkan konsep akulturasi
pada tahun 1883 ketika melakukan studi pada suku Numa salah satu suku Indian
yang menempati wilayah California, Arizona, Utah, Oregon dan Nevada. Sejak
konsep akulturasi diperkenalkan Powell, konsep ini menjadi topik menarik dalam
perbincangan para akademisi, dan banyak studi kemudian gencar dilakukakan yang
dilakukan Holmes (1886), Boas (1896) dan W. McGee (1898).59
Ketiganya
merupakan ilmuan dalam bidang etnologi atau antropologi budaya. Di awal 1910,
para sarjana antropologi mulai memerhatikan masalah akulturasi dengan melakukan
penyelidikan terhadap kehidupan masyarakat dan kebudayaan dari berbagai suku
bangsa Indian (penduduk asli Amerika) yang disebabkan pengaruh kebudayaan
orang “kulit putih”, dan juga berbagai suku bangsa di Afrika, Oceania, Filipina dan
Indonesia, dan kemudian melukiskan berbagai perubahan yang terjadi pada
kehidupan dan kebudayaan mereka.60
Pada perkembangannya akulturasi tidak hanya menjadi fokus dalam disiplin
etnologi atau antropologi budaya, tetapi telah menarik perhatian para ilmuan di
bidang sosiologi dan psikologi. Dalam bidang sosiologi Simon menulis “Social
Assimilation”,61
sedangkan dalam bidang psikologi Thomas dan Znaniecki meneliti
dan menulis tentang fenomena akulturasi di kalangan para pendatang yang berasal
dari Polandia di negara Eropa dan Amerika, dan dipublikasikan pada tahun 1918
dengan judul The Polish Peasant in Europe and America; Monograph of an
Immigration Group”.62
Kemudian di tahun 1936 terbit sebuah artikel
“Memorandum for the Study of Acculturation” tulisan kolaboratif Robert
Redfield, Linton dan Herskovits63
dan menjadi pembuka bagi studi-studi
berikutnya. Pada tahun 1951 konsep akulturasi dijadikan sebagai konsep kerja oleh
International Organization for Migration untuk mengatasi masalah para imigran
dan pengungsi dengan maksud untuk membantu mereka mengatasi shock culture
dan kesehatan mental lainnya. Kaitannya dengan kesehatan mental, seorang pakar
psikologi, Berry menulis “Immigration, Acculturation and Adaption” telah banyak
mengupas soal kesehatan mental di kalangan para imigran atau pengungsi pada
58
Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan…, h. 91. 59
J. W. Powell, Seeing Things Whole: The Essential John Wesley Powell, (Island
Press, 2004). 60
R. M. Keesing & F. M. Keesing, New Perspectives in Cultural Anthropology, (New
York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1971), h. 19. 61
S. E. Simons, “Social Assimilation”. American Journal of Sociology, vol. 6, no. 6,
1901, h. 790-822. 62
W. I. Thomas & F. Znaniecki, The Polish peasant in Europe and America:
Monograph of an immigrant group, vol. 2, (University of Chicago Press, 1918). 63
Redfield, Linton, & Herskovits, “Memorandum…, h. 149-152.
44
tahun 1997.64
Kemudian di tahun 2000, fenomena akulturasi menjadi diskursus
penting di kalangan para ilmuan ketika mengkaji studi perubahan budaya. Banyak
karya yang bermunculan pada periode ini, dua di antaranya adalah “Acculturation,
Living Successfully in Two Cultures” karya J. W. Berry pada tahun 2005,65
dan
“Rethingking the Concept of Acculturation, Implication for Theory and Research”
karya Schwartz, Unger, Zamboanga, dan Szapocznik tahun 2010.66
Sebenarnya, masalah akulturasi sudah lama dirumuskan oleh para pakar. Selain
membahas masalah metode untuk mengobservasi, mencatat dan mendeskripsikan
suatu proses akulturasi, juga ada empat masalah pokok yang berkaitan dengan
diskursus akulturasi, yaitu: (1) Unsur-unsur kebudayaan asing apakah yang mudah
diterima atau sukar diterima; (2) Unsur-unsur kebudayaan apakah yang mudah
diganti atau diubah oleh kebudayaan asing; (3) Individu-individu manakah yang
cepat menerima unsur-unsur kebudayaan asing, atau sebaliknya; (4) Ketegangan
dan krisis sosial sebagai akibat terjadinya akulturasi. Menurut Purwanto unsur
kebudayaan yang bersifat konkrit dan memiliki manfaat besar dalam kehidupan,
biasanya cenderung mudah diterima. Sementara unsur kebudayaan yang sukar
diterima biasanya yang berkaitan dengan upacara adat dan unsur kebudayaan yang
sudah berakar dari kecil. Dalam proses akulturasi juga dibahas tentang individu-
individu yang lambat atau cukup responsif menerima akulturasi. Dalam konteks ini
Purwanto mengatakan golongan muda tidak selalu lebih cepat menerima akulturasi
dari pada golongan tua. Cepat atau lambatnya seseorang dalam menerima proses
akulturasi sangat berkaitan dengan latar belakang yang melingkarinya dan
kepentingan apa yang terkait.67
Para ahli antropologi kemudian menaruh perhatian akan peristiwa terjadinya
proses akulturasi, agar dapat mengetahui dan memahami bagaiamana proses
tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan, baik perubahan sosial maupun
budaya. Sebagai salah satu bentuk proses sosial, akulturasi erat kaitannya dengan
pertemuan dua kebudayaan atau lebih. Sebagai akibat dari pertemuan tersebut,
maka kedua belah pihak saling memengaruhi dan akhirnya kebudayaan mereka
mengalami perubahan bentuk. Artinya, akulturasi hanya akan terjadi jika ada dua
kebudayaan atau lebih bertemu. Selanjutnya, ada banyak faktor yang menyebabkan
terjadinya akulturasi, di antaranya direct cultural transmissions,68
kasus-kasus mono
64
J. W. Berry, “Immigration, Acculturation, and Adaption”. Applied Psychology, An
International Review, vol. 46, 1997, h. 5-68. 65
J. W. Berry, “Acculturation: Living successfully in Two Cultures”. International
Journal of Intercultural Relations, vol. 29, no. 6, 2005, h. 697-712. 66
S. J. Schwartz, J. B. Unger, B. L. Zamboanga, & J. Szapocznik, “Rethinking the
Concept of Acculturation: Implications for Theory and Research”. American
Psychologist, vol. 65, no. 4, 2010, h. 237-251. 67
Purwanto, Kebudayaan dan Lingkungan…, h. 186-187. 68
D. Anzola & D. Rodríguez-Cárdenas, “A Model of Cultural Transmission by Direct
Instruction: An Exercise on Replication and Extension”. Cognitive Systems Research, vol.
52, 2018, h. 450-465.; S. Bar-Gill & C. Fershtman, “Integration Policy: Cultural
Transmission with Endogenous Fertility”. Journal of Population Economics, vol. 29, no. 1,
2016, h. 105-133.; C. Attias-Donfut, “Family transfers and cultural transmissions between
three generations in France”. Global Aging and Challenges to Families, 2003, h. 214-252.
45
kultural seperti ekologis dan demografis, serta modifikasi sebagai akibat pergeseran
kebudayaan, juga akulturasi bisa disebabkan oleh suatu reaksi adaptasi bentuk-
bentuk kehidupan yang tradisional.69
Akulturasi sebagai sebuah proses sosial yang erat kaitannya dengan pertemuan
dua kebudayaan atau lebih memerlukan sikap yang arif dalam menghadapi
perubahan-perubahan yang terjadi, atau dalam pengertian lain biarlah proses
akulturasi tetap berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Namun, agar dalam
perubahan yang terjadi tidak menyimpang dari akar budaya bangsa, maka
dibutuhkan suatu pedoman yang dapat menentukan arah perkembangan kebudayaan
bangsa. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 merupakan pedoman untuk
menangkal lajunya proses akulturasi agar tidak melenceng dari nilai-nilai inti
Pancasila sebagai konfigurasi kebudayaan bangsa.
Menurut Rudmin akulturasi yang selama ini dipahami sebagai bentuk yang
dapat menyatukan dua kebudayaan atau lebih, namun penomemena kontemporer
mengakibatkan sebaliknya, akulturasi menjadi pemicu benturan antar etnis,
benturan peradaban, bahkan tidak jarang terjadi perang antar suku (masyarakat
tempatan dengan pendatang).70
Kenyataan ini seperti yang terjadi pada benturan
kebudayaan di Papua atau yang sedang terjadi di Papua. Karena masyarakat Papua
heterogen, maka penyelesaian konflik harus menggunakan pendekatan antropologi
dan sosiologi budaya.71
Menurut penulis, penyelesaian dengan senjata bukan solusi
yang tepat untuk menyelesaikan masalah di Papua. Sebaiknya dilakukan dialog
dengan semua pihak terkait untuk mendapatkan solusi terbaik bagi kemaslahatan
masyarakat Papua dan semua pihak yang ada di dalamnya.
Abadi dalam penelitiannya tentang pembauran di Sumenep menemukan bahwa
perkawinan silang (cross marriage) menjadi salah satu lembaga penting yang
mampu menghasilkan pembauran yang berkualitas dan alamiah, yang pada akhirnya
menghasilkan akulturasi dan asimilasi dalam berbagai dimensi kehidupan.
Berangkat dari temuannya, Abadi mengatakan pembauran yang berkualitas hanya
akan terjadi jika masing-masing individu atau kelompok menjunjung tiggi martabat
kemanusiaan (human dignity).72
69
J. M. Waldmueller, “Agriculture, Knowledge and the „Colonial Matrix of Power‟:
Approaching Sustainabilities from the Global South”. Journal of Global Ethics, vol. 11, no.
3, 2015, h. 294-302.; W. Leimgruber, “Values, Migration, and Environment: An Essay on
Driving Forces Behind Human Decisions and their Consequences”. In Environmental
Change and its Implications for Population Migration, (Dordrecht: Springer, 2004), 247-
266.; P. L. Van den Berghe, “Australia, Canada and the United States: Ethnic Melting Pots
or Plural Societies?”. The Australian and New Zealand Journal of Sociology, vol. 19, no. 2,
1983, h. 238-252. 70
F. W. Rudmin, “Debate in Science: The Case of Acculturation”, AnthroGlobe
Journal, 2006, h. 72-73. 71
J. O. Ondawame, “West Papua: The Discourse of Cultural Genocide and Conflict
Resolution”. In Cultural Genocide and Asian State Peripheries, (New York: Palgrave
Macmillan), h. 103-138. 72
M. A. M. Abadi, “Cross Marriage (Sebuah Model Pembauran Budaya Antar
Komunitas Cina, Arab, India, Jawa dan Madura di Sumenep Kota)”. KARSA: Journal of
Social and Islamic Culture, vol. 12, no. 2, 2012, h. 132-148.
46
Menurut penulis, temuan Abadi di atas membuktikan bahwa hubungan yang
harmoni dan penuh toleransi akan menghasilkan pembauran yang alamiah, wajar
dan berkualitas. Akulturasi meniscayakan sikap toleransi dan simpati dari semua
pihak. Namun, jika ada kekuatan negara yang ikut intervensi dalam pembauran
seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintah Hindia Belanda dan Orde Baru,
maka pembauran yang dihasilkan akan semu, kualitasnya dangkal dan rentan
dengan banyak kepentingan, atau dengan kata lain pembauran yang dipaksakan itu
merendahkan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Sementara dalam konteks
Cirebon, toleransi dan keharmonisan antar komunitas etnis/ras yang terjadi pada
abad XV dan XVI layak menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat
Indonesia yang akhir-akhir ini sering mengalami kegamangan dan masalah-masalah
yang terkait dengan isu SARA.
2. Asimilasi
Konsep asimilasi telah diperdebatkan secara luas dalam ilmu sosial tentang
migrasi sejak awal abad ke-20, tetapi sekarang diterima secara luas sebagai cara
untuk menggambarkan cara-cara imigran dan pergantian musim semi ketika mereka
melakukan kontak dengan masyarakat setempat. Dalam penggunaannya saat ini,
konsep asimilasi tidak menyiratkan superioritas apapun dalam pandangan
masyarakat tuan rumah atau nilai tertentu terhadap perubahan sikap dan perilaku di
antara para imigran lintas generasi. Sebaliknya, asimilasi sekarang paling berguna
sebagai sarana untuk menggambarkan dinamika sosial.73
Asimilasi dapat dibedakan
dari akomodasi, proses kompromi yang ditandai oleh toleransi, dan dari akulturasi,
atau perubahan budaya yang diprakarsai oleh gabungan dua atau lebih sistem
budaya atau pemindahan individu dari masyarakat asli dan latar budaya ke
lingkungan sosial budaya baru. Asimilasi harus dibedakan juga dari penggabungan,
atau fusi biologis. Arti istilah seperti difusi juga sangat bervariasi dari asimilasi.
Asimilasi berasal dari kata assimilare (Latin) atau assimilation (Inggris) yang
berarti “menjadi sama” (Indonesia). Sinonim kata asimilasi adalah pembauran.
Asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi yang ditandai dengan adanya upaya-
upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara masing-
masing individu atau kelompok-kelompok manusia.74
A Modern Dictionary of
Sosiology mendefinisikan asimilasi sebagai suatu proses yang terjadi jika seorang
individu atau kelompok mengadopsi kultur atau identitas kelompok lain dan
menjadikannya sebagai bagian dari kelompok tersebut. Asimilasi juga bisa
dimaknai sebagai suatu proses saling serap dan bercampurnya kebudayaan yang
berbeda dimana masing-masing elemen saling meleburkan diri dengan kebudayaan
lainnya.75
Sementara The Cambridge Dictionary of Sociology mendefinisikan
asimilasi adalah sebagai suatu proses mengidentifikasi diri atau membuat seseorang
73
M. A. Lone, “Towards A Sociology of Assimilation: Concept, Theory, Debate and
Practice in Cultural Anthropology”. Asian Journal of Research in Social Sciences and
Humanities, vol. 3, no. 12, 2013, h. 131-166. 74
Puspito, Sosiologi Semantik…, h. 233. 75
S. Soemardjan, Streotip, Asimilasi, Integrasi Sosial, (Bandung: Cita Karya, 1976), h.
224-225.
47
menjadi bagian dari suatu kelompok, komunitas, atau warga negara tertentu. Kata
asimilasi juga diartikan sebagai sebuah proses penerimaan kenyataan baru atau
keadaan baru untuk menyesuaikan diri sebagai sebuah kesadaran yang diterima.76
Berdsarkan penjelasan di atas, asimilasi secara sederhana dalam pengertian
sosiologis didefinisikan sebagai suatu proses sosial dimana dua atau lebih individu
atau kelompok saling meleburkan diri sehingga identitas masing-masing menjadi
hilang dan terwujud kebudayaan baru yang berbeda dengan budaya aslinya.
Asimilasi mempunyai dua pengertian yang berbeda yaitu membuat seperti
atau meleburkan diri pada budaya dominan, dan yang kedua adalah mengambil atau
menggabungkan. Dalam pengertian pertama, seseorang atau suatu kelompok
masyarakat menerima bahasa, sikap perangai dan tingkah laku kelompok lain yang
dominan dan menyesuaikan dirinya dengan budaya kelompok tersebut. Adapun
dalam pengertian kedua, seseorang atau kelompok saling mengambil dan bergabung
sehingga terbentuk budaya baru.77
Semula memang istilah asimilasi hanya mengacu
pada hubungan satu arah dan satu dimensi dimana kelompok imigran melepaskan
karakteristik kebudayaan asalnya untuk kemudian meleburkan diri dengan
kebudayaan dominan.78
Namun, pada perkembangannya konsep asimilasi merujuk
pada relasi dua kelompok yang berbeda dengan masing-masing kebudayaannnya
yang kemudian masing-masing kelompok saling memengaruhi dan dipengaruhi.79
Xie dan Greenman mendefinisikan asimilasi sebagai proses sosial yang terjadi
jika ada dua atau lebih kelompok manusia dengan kebudayaaan berbeda-beda
bertemu, terjadi kontak sosial yang intensif untuk waktu yang lama sehingga
masing-masing kebudayaan tadi berubah karakteristiknya dan berubah wujudnya
menjadi kebudayaan campuran. Proses sosial ini biasanya terjadi pada kelompok
76
B. S. Turner, The Cambridge Dictionary of Sociology, (UK: Cambridge University
Press, 2006). 77
A. Asfari & A. Askar, “Understanding Muslim Assimilation in America: An
Exploratory Assessment of First & Second-Generation Muslims Using Segmented
Assimilation Theory”. Journal of Muslim Minority Affairs, 2020, h. 1-18.; S. J. Nawyn & J.
Park, “Gendered segmented assimilation: earnings trajectories of African immigrant women
and men”. Ethnic and Racial Studies, vol. 42, no. 2, 2019, h. 216-234.; C. Diehl,
“Assimilation without groups?. Ethnic and Racial Studies, vol. 42, no. 13, 2019, h. 2297-
2301. 78
R. Abramitzky, L. Boustan, & K. Eriksson, “Do Immigrants Assimilate More Slowly
today than in the past?. American Economic Review: Insights, vol. 2, no. 1, 2020, h. 125-41.;
F. M. Muchomba, N. Jiang, & N. Kaushal, “Culture, labor supply, and fertility across
immigrant generations in the United States”. Feminist Economics, vol. 26, no. 1, 2020, h.
154-178.; C. Daniel, “Language Policies, Immigrant Assimilation, and Minority Group
Advancement in the United States”. In Handbook of the Changing World Language Map,
2020, h. 2237-2259. 79
J. S. Jahangir, "Mappila Experience: Assimilation of Cultures and Legacy of Islam in
Kerala”. Studies in Indian Place Names, vol. 40, no. 3, 2020, h. 2540-2547.; B. Woo, D. D.
Maglalang, S. Ko, M. Park, Y. Choi, & D. T. Takeuchi, “Racial discrimination, ethnic-racial
socialization, and cultural identities among Asian American youths”. Cultural Diversity and
Ethnic Minority Psychology, 2020.; P. Pathak & S. Vadiya, “Role of Employee Assimilation
in Controlling Job Hopping–An Empirical Study”. Studies in Indian Place Names, vol. 40,
no. 8, 2020, h. 297-307.
48
mayoritas dan minoritas. Kelompok minoritas biasanya yang meleburkan diri pada
golongan mayoritas sehingga karakteristik kebudayaannya lama kelamaan akan
hilang dan menyatu dengan kelompok mayoritas.80
Sementara Horton dan Hunt
mendefinisikan asimilasi sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan usaha-
usaha untuk mempersatukan tindakan, sikap dan proses-proses mental dengan
mempertimbangkan kepentingan dan tujuan bersama, sekaligus usaha untuk
mengurangi perbedaan yang terdapat di antara individu atau kelompok.81
Pendapat Horton dan Hunt di atas sepertinya diperkuat oleh para ahli yang lain
seperti Harsojo mengatakan asimilasi adalah suatu proses sosial yang ditandai
dengan makin berkurangnya karakteristik masing-masing individu atau kelompok
untuk mencapai kepentingan dan tujuan yang sama.82
Senada para ahli sebelumnya,
Soekanto mengatakan asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai dengan
adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan yang terdapat pada individu atau
kelompok manusia dan memperkuat usaha-usaha untuk menyatukan langkah, sikap
dan ide untuk mencapai kepentingan bersama.83
Sekalipun banyak pendapat terkait definisi asimilasi, namun semua sepakat
asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila dua kelompok manusia atau lebih
dengan latar belakang kebudayaaan yang berbeda saling bertemu dan berinteraksi
secara intensif untuk waktu yang lama, selanjutnya kebudayaan masing-masing
golongan berubah wujudnya menjadi suatu kebudayaan baru. Biasanya asimilasi ini
terjadi pada kelompok mayoritas dan minoritas. Golongan minoritas menyesuaikan
diri dan meleburkan diri dalam golongan mayoritas sehingga lambat laun
kehilangan identitas kebudayaan dan melebur dalam kebudayaan mayoritas.84
Idi dan Huda berpendapat bahwa asimilasi akan cepat terjadi jika kelompok
pendatang mau berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara
ekonomi, sosial-budaya, politik maupun aspek lainnya, serta menghilangkan
prasangka dan diskriminasi terhadap penduduk asli. Dalam konteks Indonesia, jenis
asimilasi sebagaimana pendapat Idi dan Huda telah terjadi di Bangka, baik di kota-
kota maupun pedesaan. Di sana etnis Tionghoa relatif dapat melebur dengan
masyarakat pribumi dan mendapat perlakuan yang baik.85
Contoh kasus tersebut
menandakan bahwa sekalipun kontak sosial antar dua kelompok masyarakat dengan
kebudayaan masing-masing berbeda dan berlangsung intensif belum tentu terjadi
suatu proses asimilasi jika di antara kelompok yang berbeda itu tidak ada sikap
saling toleransi dan menghargai di antara mereka. Tidak hanya terjadi di Bangka,
etnis Tionghoa di Surakarta sebagaimana studi Sutirto mengatakan etnis Tionghoa
80
Y. Xie & E. Greenman, “The social context of assimilation: Testing implications of
segmented assimilation theory”. Social Science Research, vol, 40, no. 3, 2011, h. 965-984. 81
P. B. Horton & C. L. Hunt, Sociology (New York: McGraw-Hill, 1976). 82
Harsojo, Pengantar Antropologi, (Bandung: Binacipta, 1967), h. 191. 83
Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 88. 84
Abadi, “Cross Marriage…, h. 132-148. 85
A. Idi & N. Huda, Cina-Melayu di Bangka, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), h.
267-269.
49
di Surakarta sekalipun bergaul secara intensif dengan etnis Jawa, tatapi banyak juga
yang belum terintegrasi ke dalam masyarakat dan kebudayaan Jawa.86
Pada prakteknya istilah asimilasi dan akulturasi sering tumpang tindih, bahkan
kedua istilah ini sering digunakan untuk mengartikan obyek yang sama. Para ahli
sosiologi sering menggunakan istilah asimilasi,87
sedangkan ahli antropologi
menggunakan istilah akulturasi.88
Cole mengatakan asimilasi merupakan proses
akulturasi yang paling ekstrim, sebab ketika terjadi kontak budaya antar dua
kelompok atau lebih, salah satu kelompok mengabaikan atau meninggalkan budaya
asalnya untuk kemudian mengadopsi budaya baru dalam kehidupannya.89
Rokhani, Salam dan Rochani-Adi, dalam karya mereka yang mengkaji
konstruksi identitas etnis Tionghoa melalui difusi budaya membuat istilah asimilasi,
akulturasi dan difusi semakin bias. Mereka banyak menggunakan istilah difusi
dalam menjelaskan Gambang Kromong yang menjadi fokus kajian sebagai wujud
budaya hibrid yang merupakan hasil akulturasi antara budaya Tionghoa dan budaya
pribumi. Penelitian mereka mengatakan kesenian Gambang Kromong merupakan
hasil difusi budaya di daerah Jakarta. Kesenian ini merupakan campuran dari
berbagai unsur budaya, juga merupakan proses integrasi budaya yang menggunakan
strategi difusi budaya. Bentuk difusi budaya dapat dilihat dari adaptasi atas bentuk
instrumen, tangga nada, lagu-lagu yang dipentaskan, maupun fungsi dari
pertunjukan gambang kromong itu sendiri.90
Dari beberapa definisi di atas, maka ada beberapa indikator dalam asimilasi
yaitu: (1) ada individu atau kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda;
(2) Antar individu atau kelompok tersebut terjadi kontak sosial yang intensif dalam
jangka waktu yang lama; (3) Masing-masing pihak saling menyesuaikan diri dan
meleburkan diri; (4) Terjadinya perubahan budaya pada masing-masing individu
atau kelompok; (5) Terwujudnya kebudayaan baru yang berbeda dengan
kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Beberapa konsep
asimilasi dalam bentuk gambar adalah sebagai berikut:
86
T. W. Sutirto, Perwujudan Kesukubangsaan Kelompok Etnik Pendatang, (Pustaka
Cakra, 2000). 87
J. E. Trimble, “Introduction: Social change and acculturation”. In Acculturation:
Advances in Theory, Measurement, and Applied Research, vol. 10, 2003, h. 3-13. 88
M. J. Herskovits, “The Significance of the Study of Acculturation for
Anthropology”. American Anthropologist, vol. 39, no. 2, 1937, h. 259-264. 89
N. L. Cole, “What is the Meaning of Acculturation? Understanding Acculturation
and How it Differs from Assimilation”. 2018. 90
U. Rokhani, A. Salam, & I. Rochani-Adi, “Konstruksi Identitas Tionghoa melalui
Difusi Budaya Gambang Kromong: Studi Kasus Film Dikumenter Anak Naga Beranak
Naga”. Resital: Jurnal Seni Pertunjukan (Journal of Performing Arts), vol. 16, no. 3, 141-
152.
50
Kebudayaan A+B Kebudayaan
A B
Gambar 1. Kebudayaan A dan Kebudayaan B bertemu dalam Masyarakat, sehingga
menghasilkan suatu kebuadayaan baru (A+B)
Kebudayaan A Kebudayaan B
Kebudayaan AB
Gambar 2. Pembauran dua unsur sosial yang berbeda dan menghasilkan suatu unsur
yang baru
+ =
Gambar 3. Pembaruan dua unsur sosial yang berbeda akan menghasilkan suatu
ukuran yang baru
51
Menurut Tumanggor ada beberapa faktor penghambat dan pendukung proses
asimilasi.91
Di antara faktor penghambat proses asimilasi, yaitu: 1) Pengetahuan
yang kurang terhadap unsur kebudayaan yang dibawa pendatang ataupun penduduk
asli. 2) Sifat takut terhadap kebudayaan yang dihadapi. 3) Perasaan ego dan
superioritas terhadap kebudayaan sendiri dibanding kebudayaan lain. Adapun
beberapa faktor pendukung proses asimilasi, yaitu: 1) Faktor toleransi, yaitu sikap
saling menerima dan menghormati kebudayaan kelompok lain. 2) Faktor
kemanfaatan timbal balik, yaitu saling memberikan manfaat kepada masing-masing
pihak. 3) Faktor simpati, yaitu sikap saling menghargai dan memperlakukan secara
baik kelompok lain. 4) Faktor perkawinan. Faktor yang terakhir yakni perkawinan
sudah dibuktikan Abadi dalam penelitiannya bahwa perkawinan silang (cross
culture) adalah lembaga yang mampu menghasilkan pembauran yang berkualitas.92
3. Difusi
Difusi kebudayaan adalah persebaran budaya suatu kelompok sosial kepada
kelompok yang lain. Difusi kebudayaan terjadi jika budaya-budaya atau norma-
norma yang dimiliki suatu kelompok masyarakat mengalami persebaran ke wilayah
atau kelompok lain.93
Melalui difusi kebudayaan, cakrawala atau wawasan
seseorang diperluas dan menjadi lebih kaya secara budaya. Terjadinya pencampuran
budaya dunia melalui berbagai etnis, agama, dan kebangsaan hanya meningkat
dengan beberapa di antaranya; transportasi, teknologi informasi dan komunikasi
yang semakin modern.
Ada beberapa contoh difusi kebudayaan yang bisa penulis kemukakan dalam
kaitannya dengan kemajuan teknologi modern, di antaranya; kita dapat dengan
mudah berkomunikasi setiap hari via media sosial seperti whatsapp, twitter,
instagram, facebook dan sebagainya dengan seseorang yang tinggal jauh dari kita.
Selain itu, melalui youtube kita juga bisa mengenal salah-satu jenis masakan Jepang
yang terkenal yaitu susi, sekaligus bagaimana cara membuatnya. Artinya, di era
globalisasi seperti saat ini, setiap orang bisa mengambil ilmu dan manfaat dari
kebudayaan asing yang dilihatnya dari media sosial maupun alat komunikasi
lainnya. Dalam konteks ini teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi
sarana difusi kebudayaan yang ampuh. Namun, kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi di era globalisasi selain berdampak positif, juga mengandung hal-hal
negatif kepada masyarakat. Pada akhirnya difusi kebudayaan dapat merubah cara
atau pola hidup seseorang.
Ragam persoalan kebudayaan yang muncul di era globalisasi selain yang
dijelaskan di atas, misalnya adalah menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme,
tergerusnya budaya asli atau budaya lokal, manusia cenderung individualis, dan
beberapa gaya hidup yang kadang tidak sesuai dengan budaya lokal.94
Ngafifi
mengibaratkannya seperti dua sisi mata uang, kemajuan teknologi di satu sisi
91
Tumanggor dkk., Ilmu Sosial & Budaya…, h. 63. 92
Abadi, “Cross Marriage…, h. 132-148. 93
S. Soemardjan, Perubahan Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1991). 94
S. Suneki, “Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah”. CIVIS, vol. 2,
no. 1, 2012, h. 307-32.
52
mendatangkan banyak manfaat, namun di sisi lain juga menimbulkan kemudharatan
yang tidak kalah besar dengan manfaatnya. Teknologi, selain mempermudah
manusia dalam menjalani kehidupan, juga mengancam kerusakan lingkungan,
dekadensi moral, global warming, dan lain sebagainya. Ada wajah ganda dalam
teknologi, suatu saat bisa menjadi teman, dan di saat yang lain bisa menjadi
musuh.95
Sementara kalau kita mengacu pada abad sebelum pertengahan, budaya
yang dimiliki suatu kelompok biasanya dibawa oleh pedagang yang melakukan
perjalanan jauh untuk menjual dagangannya.96
Pada saat terjadi migrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok manusia ke
berbagai penjuru dunia, maka pada saat itu pula terjadi persebaran unsur-unsur
kebudayaan. Proses demikian dalam ilmu antropologi dikenal sebagai difusi
(diffusion). Menurut Koentjaraningrat proses difusi adalah proses penyebaran unsur-
unsur kebudayaan ke seluruh penjuru dunia. Salah satu bentuk difusi adalah
persebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain dilakukan oleh
kelompok manusia yang bermigrasi.97
Ada beberapa proses difusi, di antaranya
adalah persebaran unsur-unsur kebudayaan yang berdasarkan pertemuan-pertemuan
antara individu-individu dalam suatu kelompok manusia dengan individu kelompok
tetangga. Pertemuan antara kelompok ini dapat berlangsung dengan berbagai cara,
salah satunya adalah bentuk hubungan yang disebabkan karena perdagangan.
Unsur-unsur kebudayaan asing dibawa oleh para pedagang masuk ke dalam
kebudayaan penerima dengan tidak disengaja dan tanpa paksaan atau secara damai.
Namun, terdapat pula pemasukan unsur-unsur budaya asing secara paksa yang
biasanya disebabkan karena peperangan dan serangan penaklukan yang berakibat
pada masuknya unsur-unsur kebudayaan asing dan mulailah proses akulturasi.98
Berawal dari ketertarikan untuk mengetahui mengapa di berbagai daerah
sering ditemukan unsur-unsur budaya yang sama, baik dalam bentuk maupun isinya
walau letak mereka berjauhan. Dalam konteks tersebut, studi difusi kebudayaan ini
dimulai. Migrasi kelompok manusia yang sudah terjadi dan dilakukan sejak dulu
menyebabkan unsur-unsur budaya tersebar. Pada perkembangan kemudian, ternyata
persebaran budaya tidak harus diikuti dengan perpindahan manusianya. Di era
sekarang, persebaran budaya bisa dilakukan melalui media komunikasi seperti
buku, surat kabar, majalah dan berbagai media audiovisual. Penelitian Gilhuly
menemukan adanya beberapa persamaan pada unsur-unsur kebudayaan di daerah-
daerah yang berlainan sebagai akibat terjadinya persebaran budaya atau cultural
diffusion. Persebaran budaya dianggap sebagai unsur yang penting dalam
95
M. Ngafifi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial
Budaya”. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, vol. 2, no. 1, 2014, h. 33-
47. 96
M. Scholze, “Trading Cultures: Berbers and Tuareg as Souvenir Vendors Marko
Scholze and Ingo Bartha”. In Between Resistance and Expansion: Explorations of Local
Vitality in Africa, vol. 18, 2004, h. 69.; L. A. Babb, “Mirrored Warriors: On the Cultural
Identity of Rajasthani Traders”. International Journal of Hindu Studies, vol. 3, no. 1, 1999,
h. 1-25. 97
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, h. 199. 98
J. Al Wekhian, “Acculturation Process of Arab-Muslim Immigrants in the United
States”. Asian Culture and History, vol. 8, no. 1, 2016, h. 89-99.
53
perkembangan makhluk manusia.99
Proses menyebar tersebut yang kemudian
membuat bangsa-bangsa saling berhubungan dan memengaruhi.
Menurut aliran difusionisme kebudayaan manusia itu sumbernya satu, dan
berada di satu tempat tertentu, yaitu pada saat manusia pertama kali ada di muka
bumi. Kemudian kebudayaan induk tadi berkembang, menyebar dan “pecah” karena
pengaruh lingkungan atau masa yang berbeda menjadi beberapa kebudayaan baru.
Kebudayaan-kebudayaan yang “pecah” tadi kemudian terus bergerak dan berpindah
dari satu tempat ke tempat lain sehingga bertemu dan berhubungan dengan
kebudayaan lain dan terjadi proses saling memengaruhi.100
Teori heliolithic yang dipelopori oleh Smith101
dan Perry102
mengatakan bahwa
sejarah kebudayaan manusia bermula dari Mesir yang kemudian bergerak ke
daerah-daerah sekitar Laut Tengah, Afrika, India, Indonesia, Polinesia dan ke
Amerika. Mereka beralasan bahwa kebudayaan Mesir kuno yang tersebar di negara-
negara itu nampak pada bangunan-bangunan batu besar atau megalith dan juga pada
kompleks unsur-unsur keagamaan yang berpusat pada penyembahan matahari, atau
helios. Pandangan Smith yang Mesir sentris karena ia banyak melakukan penelitian
terhadap kebudayaan Mesir kuno. Ia juga banyak mendapatkan persamaan unsur-
unsur kebudayaan besar yang ada di daerah lain dengan yang ditemukannya di
Mesir. Smith akhirnya menyimpulkan bahwa unsur-unsur kebudayaan yang tersebar
itu berasal dari Mesir.103
Namun, teori ini banyak mendapat kecaman, yang salah
satunya datang dari seorang antropolog Amerika bernama Lowiemenyatakan
bahwa teori heliolithic merupakan teori difusi yang ekstrim, tidak sesuai dengan
fakta di lapangan, baik dipandang dari sudut hasil-hasil penggalian ilmu prasejara
maupun dari sudut konsep-konsep tentang proses difusi dan persebaran unsur-unsur
kebudayan antara bangsa-bangsa yang telah diterima oleh kalangan ilmu
antropologi waktu itu.104
Penelitian tentang difusi juga dipelopori oleh seorang ilmuwan Perancis
bernama Tarde dengan turut mengenalkan konsep hukum imitasi yang menyatakan
bahwa seseorang belajar dengan cara meniru orang lain. Dengan demikian difusi
adalah proses sosial dari sebuah jaringan komunikasi antar pribadi
(interpersonal).105
Kemudian diteruskan oleh ilmuwan dari Inggris yang bernama
99
K. Gilhuly, R. Ackerman, J. N. Adams, F. Ahl, J. Alvares, B. Anderson, W. S.
Anderson et al., “Cultic Prostitution: A Case Study in Cultural Diffusion”. In Erotic
Geographies in Ancient Greek Literature and Culture, vol. 51, no. 1/2, (New York: Center
for Hellenic Studies, 2018), h. 1-10. 100
F. Lissoni, “International Migration and Innovation Diffusion: An Eclectic
Survey”. Regional Studies, vol. 52, no. 5, 2018, h. 702-714. 101
G. E. Smith, In the Beginning: Origin of Civilisation, (New York: Morrow, 1928). 102
W. J. Perry, The Children of the Sun, (London: Methuen, 1923).; Lihat juga W. J.
Perry, Gods and Men. The Attainment of Immortality, (London: G. Howe ltd., 1927). 103
G. E. Smith, The Influence of Ancient Egyptian Civilization in the East and in
America, (America: The University Press, 1916). 104
R. H. Lowie, The History of Ethnological Theory, (New York: Holt, Rinehart &
Winston, 1937). 105
G. Tarde & J. M. Baldwin, “Imitation and Creativity”. The Creativity Reader, 2019,
h. 173.; Lihat juga P. Beirne, “On Gabriel Tarde, Penal Philosophy”. In Classic Writings in
54
Simmel yang memperkenalkan penelitiannya bahwa individu merupakan anggota
sebuah sistem namun tidak terikat kuat pada sistem itu.106
Tradisi penelitian difusi
sudah mulai ramai dilakukan pada pertengan tahun 1940. Dalam sejarahnya,
disiplin ilmu sosiologi dianggap sebagai pionir dalam penelitian difusi.
Ghazali dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa teman dan media berperan
penting dalam proses difusi budaya transeksual di kalangan pelajar laki-laki.
Penelitian ini dilakukan di empat universitas yang berbeda pada tahun 2007-2009.
Globalisasi dianggap menjadi penggerak kepada berlakunya difusi budaya dalam
masyarakat. Budaya transeksual sekalipun bertentangan dengan budaya dan nilai-
nilai lokal, namun keberadaannya tidak bisa dihapuskan karena mendapatkan
dukungan dari infrastruktur yaitu media komunikasi yang terus menerus
mempertontonkan gaya hidup mereka baik lewat film dan sebagainya.107
Beberapa riset kolaboratif sebagaimana yang dilakukan Olson,108
Soete109
Benhabib dan Spiegel,110
tentang pengaruh difusi teknologi pada pola hidup
manusia menyatakan secara sosiologis, salah satu aspek yang memengaruhi prilaku,
aktivitas dan tindakan manusia adalah teknologi. Teknologi mampu mengubah pola
relasi antar manusia. Keberadaan teknologi akan sangat memengaruhi prilaku
manusia. Kemajuan teknologi mewujudkan masyarakat digital dalam berbagai
aspek kehidupan manusia. Munculnya berbagai alat-alat cangih di bidang informasi
dan komunikasi seperti satelit, bioteknologi, di bidang pertanian, di bidang
kesehatan dan rekayasa genetika menunjukkan teknologi masyarakat itu maju.
Di era globalisasi saat ini, indikator kemajuan suatu negara adalah pada
penguasan teknologi. Negara-negara maju menjadi adikuasa, kaya raya dan disegani
karena memiliki teknologi canggih. Sebaliknya, jika negara itu terbelakang
teknologinya maka akan tertinggal dan ditinggalkan. Manusia sekarang sudah
benar-benar menjadi budak teknologi. Berdasarkan survey Secure Envoy (2012)
terhadap 1000 orang di UK menyimpulkan bahwa mahasiswa sekarang mengalami
nomophobiaperasaan cemas dan takut. 66 persen responden mengaku tidak bisa
Law and Society: Contemporary Comments and Criticisms, (London & New York:
Routledge, 2017), h. 21-28. 106
J. McCole, “Georg Simmel: Decentering the Self and Recovering Authentic
Individuality”. The Germanic Review: Literature, Culture, Theory, vol. 94, no. 2, 2019, h.
151-162.; O. Lizardo, “Simmel‟s Dialectic of Form and Content in Recent Work in Cultural
Sociology”. The Germanic Review: Literature, Culture, Theory, vol. 94, no. 2, 2019, h. 93-
100. 107
S. Ghazali, J. Mapjabil, A. Nor, N. Samat, & J. Jaafar, “Difusi Ruangan Budaya
Transeksualisme dan Imaginasi Geografi Pelajar Lelaki Berpenampilan Silang di Universiti
Tempatan Malaysia”. E-Bangi Journal of Social Science and Humanities, vol. 7, no. 1,
2012, h. 252-266. 108
K. E. Olson, M. A. O‟Brien, W. A. Rogers, & N. Charness, “Diffusion of
Technology: Frequency of Use for Younger and Older Adults”. Ageing International,
vol. 36, no. 1, 2011, h. 123-145.; 109
L. Soete, “International Diffusion of Technology, Industrial Development and
Technological Leapfrogging”. World Development, vol. 13, no. 3, 1985, h. 409-422. 110
J. Benhabib & M. M. Spiegel, “Human capital and technology diffusion”.
In Handbook of Economic Growth, vol. 1, 2015, h. 935-966.
55
hidup tanpa telepon selular. Jumlah ini meningkat pada responden usia 18-24 tahun
yakni sebanyak 77 persen.111
Berdasarkan penelitian Wiyoso, proses difusi juga terjadi pada musik
Karawitan. Proses difusi dari instrumen musik dapat dilihat dengan adanya rebab
dalam gamelan Jawa. Instrumen rebab juga dapat ditemui di negara-negara lain
seperti Arab, Maroko, Philipina dan Eropa. Sekalipun di setiap negara rebab itu
memiliki nama yang berbeda-beda dan mungkin telah dimodifikasi, namun pada
prinsipnya instrumen tersebut asal mulanya samainstrumen spike fiddle
instrumen bersenar yang gagangnya melewati diametral melalui resonator dan
dimainkan dengan busur. Sama seperti alat musik bonang di Indonesia yang juga
memiliki nama berbeda-beda. Ada bonang di Jawa, talempong di Minang dan
trompong di Bali.112
Dalam konteks bangsa yang majemuk, komunikasi lintas
budaya menjadi penting untuk meminimalisir munculnya konflik antar etnis.
Dengan mempelajari komunikasi budaya, seseorang akan mampu besikap bijak dan
moderat dalam menghadapi perbedaan-perbedaan, serta lebih berhati-hati dalam
membangun relasi sosial.113
Komunikasi antar budaya adalah komunikasi atau
dialog yang dilakukan oleh masing-masing pribadi atau kelompok yang memiliki
budaya yang berbeda.114
B. Kedatangan Etnis Tionghoa: Jejak Cheng Ho dan Muslim Tionghoa
Melihat beberapa peninggalan sejarah seperti artefak dan bahan sejarah, baik
sumber lokal maupun tulisan dalam bahasa asing karya para sarjana, banyak
mengaitkan antara kebudayaan Tionghoa di Nusantara, khususnya Indonesia yang
sebelumnya Hindia-Belanda dengan jejak kunjungan Cheng Ho dan Tionghoa
Muslim lainnya. Oleh karena itu, bagian ini ingin menggambarkan bahwa Cheng
Ho dan Tionghoa Muslim memang berperan dalam penciptaan budaya dan
peradaban Indonesia, melalui penyebaran Islam, dan dalam pengembangan
kerukunan antar agama di abad 15 dan 16. Bagian ini tidak secara detail
memberikan catatan tentang sejarah Cheng Ho dan kedatangannya di Nusantara
(Indonesia), tetapi lebih pada perdebatan soal fakta sejarah dan cerita-cerita rakyat
setempat tentang kehadirannya di Indonesia abad ke-15 dan sedikit menggambarkan
bagaimana masyarakat lokal memandang sosok Cheng Ho yang luar biasa dalam
penyebaran agama Islam. Sudah dikenal luas dalam masyarakat Muslim Indonesia
bahwa Islam dibawa ke kepulauan terutama oleh pedagang Arab, Sufi Persia,
pedagang Gujarat, atau guru India. Menurut Al Qurtuby, hanya segelintir
111
E. P. Yildiz, M. Çengel, & A. Alkan, “Investigation of Nomophobia Levels of
Vocational School Students According to Demographic Characteristics and Intelligent
Phone Use Habits”. Higher Education Studies, vol. 10, no. 1, 2020, h. 132-143.; C. Yildirim
& A. P. Correia, “Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of
a self-reported questionnaire”. Computers in Human Behavior, vol. 49, 2015, h. 130-137. 112
J. Wiyoso, “Pengaruh Difusi dalam Bidang Musik Terhadap Karawitan, Harmonia”.
Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni, vol. 3, no. 2, 2002. 113
M. Syarifah, “Budaya dan Kearifan Dakwah”. Jurnal al-Balagh, vol. 1, no. 1, 2016,
h. 23-24. 114
A. Liliweri, Meaning of Culture and Intercultural Communication, (Yokyakarta:
LKIS, 2003), h. 12-13.
56
cendekiawan, sejarawan, dan ilmuwan sosial yang mengakui keberadaan dan
kontribusi Tionghoa Muslim dalam proses islamisasi Indonesia.115
Bagian ini,
kemudian, akan mencoba untuk menyajikan tokoh-tokoh sejarah Tionghoa Muslim
di bagian utara Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya selama abad ke 15
dan 16, serta sedikit mendiskusikan dampak dari kunjungan Cheng Ho dalam proses
pembentukan Tionghoa-Jawa atau budaya Muslim Indonesia.
Ma Huan dalam karyanya Ying-yai Sheng-Ian: The Overall Survey of the
Ocean's Shores (1433), menulis bahwa di Jawa (Jawa Timur) ada tiga jenis orang,
yaitu: pertama, orang-orang Muhammad, yang datang dari Barat dan telah mapan,
serta pakaian dan makanan mereka bersih dan layak. Kedua, orang Tionghoa yang
semua datang dari Canton, Chang-chou dan Ch‟uan-chou.116
Mereka adalah orang-
orang yang melarikan diri dari tiga daerah tersebut dan menetap Jawa. Disebutkan
juga apa yang mereka makan dan gunakan juga sangat baik dan banyak dari mereka
telah mengadopsi agama Muhammad dan menjalankan ajarannya. Ketiga, penduduk
asli (pribumi), yang sangat jelek dan tidak sopan, mereka pergi dengan kepala tanpa
lengan dan kaki telanjang dan percaya pada setan. Makanan orang-orang ini sangat
kotor dan buruk, misalnya ular, semut, serangga dan cacing, yang disimpan sesaat
sebelum dibakar dan lalu dimakan. Kemudian mereka memelihara anjing di rumah,
memakannya dan tidur bersama mereka, tanpa merasa jijik sama sekali.117
Gambaran tentang tiga jenis orang yang tinggal dan menetap di Jawa
sebagaimana dalam tulisan Ma Huan, dikomentari oleh Al Qurtuby dengan
mengatakan bahwa meskipun komentar dan pandangan Ma Huan tentang
“penduduk asli” terlihat merendahkan masyarakat setempat, yang ia gambarkan
sebagai masyarakat tidak beradab, namun kisahnya tentang keberadaan Tionghoa
Muslim di Jawa layak untuk dipertimbangkan dengan cermat,118
sebab Ma Huan
adalah seorang Tionghoa Muslim yang menemani Cheng Ho dalam perjalanan
keempatnya di Laut Selatan (1413-1415) yang melaporkan selama perjalanan
mereka melalui Jawa Timur bahwa penduduknya terdiri dari penduduk asli (Jawa),
Muslim dan Tionghoa, banyak dari mereka adalah Muslim. Kemudian, sebuah teks
Tionghoa kontemporer Xiyang Fanguo Zhi (Records of the Foreign Countries in the
Western Ocean), sebagaimana dikutip oleh para sejarawan dan sinolog Prancis,
Lombard dan Salmon,119
bahkan sampai sejauh mengatakan bahwa semua orang
Tionghoa ini adalah Muslim. Namun, menurut Al Qurtuby hal tersebut sangat
berlebihan untuk mengatakan bahwa semua orang Tionghoa yang tinggal di Jawa
115
S. Al Qurtuby, “The Imprint of Zheng He and Chinese Muslims in Indonesia‟s
Past”. Zheng He and the Afro-Asian World, h. 171-186. 116
Chang-chou dan Ch‟uan-chou terletak di Fukien, tidak jauh dari Amoy. 117
Ma Huan, Ying-yai Sheng-Ian: The Overall Survey of the Ocean's Shores (1433).
Translated by J. V. G. Mills. Edited by Feng Ch‟eng Chun, (Cambridge: The University
Press for the Hakluyt Society, 1970), h. 93.; Lihat juga penjelasan yang senada dalam karya
W. P. Groeneveldt, Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese
Sources, (Jakarta: Bhratara, 1960), h. 49. 118
Al Qurtuby, “The Imprint…, h. 171-186. 119
D. Lombard & C. Salmon, “Islam and Chineseness”. Indonesia, no. 57, 1993, h.
115-131.
57
Timur, terutama di daerah Surabaya, Gresik dan Tuban selama abad 15 adalah
pengikut agama Muhammad atau menganut agama Islam.120
Soal pelayaran dan pendaratan armada Cheng Ho, Tingyu mengatakan bahwa
telah melibatkan 62 kapal besar dan 225 kapal lainnya bersama dengan 27.550 awak
kapal, pejabat, pembuat peta, astronom, dokter, pengkhotbah, ahli etnografi, tabib
tradisional, dan sebagainya.121
Dari 1405 hingga 1433, Cheng Ho melakukan tujuh
kali pelayaran dan mengunjungi lebih dari 37 negaradari pelabuhan Indonesia,
terutama Palembang, Cirebon, Banten, Gresik, Surabaya dan Semarang, ke Ceylon,
Kocin, Calikut, Ormuz, Jeddah, Magadishu dan Malindi, dari Champa ke India, dari
Teluk Persia ke Laut Merah dan pantai Kenya. Selama perjalanannya, Cheng Ho
ditemani Heo Shien, Ma Huan dan Fei Shien, semuanya adalah Muslim, yang
melayani sebagai wakil dan sekretarisnya. Kemudian seorang juru bicara yang fasih
berbahasa Arab bernama Ha San (imam masjid Sin An/Changan). Menurut Menzies
Cheng Ho adalah seorang Muslim yang taat dan sosok yang kuat selain menjadi
seorang prajurit yang tangguh dan penasihat terdekat Kaisar Yongle.122
Literatur mencatat bahwa Cheng Ho melakukan pelayaran sebanyak tujuh kali.
Pelayaran pertama (1405-1407) adalah dari Nanjing ke Calicut, Champa, Jawa,
Sriwijaya, Sumatra, dan Ceylon; pelayaran kedua (1407-1409) adalah perjalanan ke
India dan untuk menginstal raja baru Calicut; pelayaran ketiga (1409-1411) adalah
ke Champa, Temasek, Malaka, Sumatra (Samudra dan Tamiang), dan Ceylon;
pelayaran keempat (1413-1415) adalah ke Champa, Jawa, Sumatra, Malaya,
Maladewa, Ceylon, India, dan Hormuz; pelayaran kelima (1417-1419) tujuannya
adalah Champa, Jawa, Palembang, Aden, Mogadishu, Brawa, dan Malindi di pantai
barat Afrika; pelayaran keenam (1421-1422) adalah ke Afrika dan seluruh dunia
termasuk Amerika;123
dan terakhir pelayaran ketujuh (1431-1433) adalah ke
Vietnam Selatan, Surabaya, Palembang, Malaka, Samudra, Ceylon, Calicut, Afrika,
dan Jeddah.124
Kemudian, menurut laporan Ma Huan, Tionghoa Muslim yang tinggal di
pantai utara Jawa sebagian besar berasal dari Canton, Changzhou, Quanzhou dan
tempat-tempat lain di Tiongkok selatan yang telah meninggalkan negara mereka
karena berbagai alasan,125
termasuk motivasi politik dan ekonomi. Tidak sedikit
juga studi yang berhubungan dengan orang Tionghoa di Batavia dan Jawa
120
Al Qurtuby, “The Imprint…, h. 171-186. 121
Z. Tingyu, “Ming shi (History of the Ming Dynasty)”. Beijing: Zhonghua shuju, vol.
285, no. 173, 1974.; Pelayaran dan pendaratan armada Cheng Ho di Nusantara juga dapat
dilihat dalam beberapa karya relevan. Lihat J. L. Nio, Tiongkok Sepandjang Abad,
(Djakarta: Gunung Agung, 1952).; Kong Yuanzhi, Sam Po Kong dan Indonesia, (Jakarta:
CV. Haji Masagung, 1996). 122
G. Menzies, 1421: The Year China Discovered America, (New York: Perennial.
2003), h. 21. 123
Menzies, 1421: The Year China…, h. 21. 124
Kong Yuanzhi, Muslim Tionghoa Cheng Ho, (Jakarta: Pustaka Populer Obor,
2000).; J. Widodo, “Admiral Zheng He and pre-Colonial Coastal Urban Development in
Southeast Asia”. Inaugural Lecture organized by Friends of Zheng He Society, (Singapore:
unpublis, 2003). 125
Ma Huan, Ying-yai Sheng-lan:…, h. 93.
58
(Indonesia), misalnya yang dilakukan Carey126
dan Blusse127
yang juga memilih
Tiongkok bagian selatan (Canton dan Hakka) sebagai yang mendominasi di antara
tempat asal imigran. Dalam konteks ini, jika dilihat dari beberapa sumber
mengatakan bahwa Ma Huan bukan satu-satunya pengembara yang menyaksikan
dan mencatat keberadaan komunitas Tionghoa Muslim pada masa pra kolonial. Lain
halnya dengan yang awal seperti Tome Pires, Edmund Scott, Cornelis de Houtman
dan Ibn Battutah juga mengakui keberadaan Tionghoa Muslim selama periode
tersebut.128
Kedatangan Tionghoa Muslim, khususnya di Jawa awal abad ke-17, juga
dikonfirmasi oleh John Jourdain yang mengunjungi Banten pada tahun 1614,129
dan
Cornelis Busyero pada tahun 1617. Memang, di Jawa abad 15 dan 16, Tionghoa
Muslim tidak hanya ditemukan di Jawa Timur sebagaimana catatan Ma Huan
selama kunjungannya, tetapi di sepanjang pantai utara Jawa termasuk Jawa Barat.
Loedewicks, yang mengunjungi Banten pada abad 16,130
juga menyaksikan
kehadiran Tionghoa Muslim, yang disebut Geschoren Chineezen (orang Tionghoa
yang dicukur) dalam dokumen VOC. Demikian juga Ibn Battutah, melaporkan
keberadaan komunitas Tionghoa Muslim di wilayah pesisir Jawa dan Asia
Tenggara.131
Selain itu, Lombard dan Salmon dalam karya mereka memberikan
keterangan tentang Tionghoa Muslim selama era kolonial Belanda, khususnya yang
ada di Jawa dan Sumatera, serta di beberapa wilayah lain Indonesia.132
Al Qurtuby selama dalam penelitiannya di Jawa utara, seperti Banten, Cirebon,
Surabaya, Tuban, Kudus, Jepara, Demak, Jakarta, dan di tempat lain tentang peran
Tionghoa Muslim dalam penyebaran Islam di Jawa (Indonesia) menemukan banyak
cerita dan fakta sejarah yang mengejutkan tentang keberadaan Tionghoa Muslim,
termasuk Cheng Ho.133
Al Qurtuby menemukan ada kisah tokoh sejarah karismatik
Tionghoa Muslim yang terkait dengan ekspedisi Cheng Ho, juga yang berkontribusi
pada penciptaan budaya Tionghoa Muslim-Indonesia/Jawa dan islamisasi. Al
Qurtuby mencontohkan dalam Kesultanan Demak, ada yang dikenal dengan nama
Demak Bintoro yang menurutnya patut mendapat perhatian khusus karena peran
sentralnya dalam menggulingkan Kerajaan Hindu-Buddha Majapahit sekitar 1478.
126
P. Carey, “Changing Javanese Perceptions of the Chinese Communities in Central
Java, 1755-1825”. Indonesia, vol. 37, 1984, h. 1-47. 127
Lihat Leonard Blusse, Strange Company: Chinese Settlers, Mestizo Women, and the
Dutch in VOC Batavia, (Amsterdam: Foris Publication, 1988). 128
G. E. Marrison, “The coming of Islam to the East Indies”. Journal of the Malayan
Branch of the Royal Asiatic Society, vol. 24, no. 1, 1951, h. 28-37. Al Qurtuby, “The
Imprint…, h. 171-186. 129
A. Reid, “The Structure of Cities in Southeast Asia, Fifteenth to Seventeenth
Centuries”. Journal of Southeast Asian Studies, vol. 11, no. 2, 1980, h. 235-250. 130
A. Muzzaki, “Cheng Hoo Mosque: Assimilating Chinese Culture, Distancing it from
the State”. London, UK: Crise Working Paper, no. 71, 2010, h. 1-29. 131
Lihat T. Harb, Rihlah Ibn Battutah al-Musammah Tuhfah al-Nuzzar fi Ghara‟ib al-
Amsar wa Aja‟ib al-Asfar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002). 132
Lombard & Salmon, “Islam and Chineseness”, h. 115-131. 133
S. Al Qurtuby, “Melaka, Cheng Ho, dan Kesadaran Sejarah Kita”, Malaysia,
Konferensi Internasional Bertajuk “Zheng He and Afro-Asian World”, 5 Januari 2014.
59
Runtuhnya Majapahit dinilai oleh Al Qurtuby sebagai yang menandai transisi dari
Hindu-Buddha ke Islam dalam sejarah sosial Jawa.134
Dengan demikian, di bawah
kendali Tionghoa Muslim, Demak adalah pusat dalam menyebarkan supremasi
Islam atas Banten, Cirebon, Jepara, Lasem, Tuban, Gresik dan Surabaya, yang
semuanya menjadi kesultanan Islam kecil. Pendiri Demak, Raden Patah sendiri
diidentifikasi sebagai seorang Tionghoa Muslim, sebagian mengatakan ia adalah
seorang Tionghoa Totok, dan sebagian yang lain menganggapnya peranakan.135
Kemudian, Al Qurtuby dalam penelitian juga mencatat beberapa tokoh
Tionghoa Muslim lain, di antaranya Liem Mo Han (Babah Liem)136
secara luas
dikenal oleh orang Jawa tidak hanya sebagai pemimpin Tionghoa lokal selama
perjuangan Demak tetapi juga sebagai arsitek dari beberapa masjid di Jawa terutama
masjid terkenal Mantingan di Jepara (dekat Demak). Selain Babah Liem, para
pemimpin Tionghoa Muslim terkenal berpengaruh lainnya di awal abad 16
termasuk Coa Mie An dan Gouw Eng Cu yang tinggal di Lasem, dekat Demak. Cie
Gwie Wan, tangan kanan Sultan Hadlirin,137
sang suami dari ratu Jawa yang
terkenal Ratu Kalinyamat, serta pendiri industri ukiran seni ukiran kayu dan patung
di Jepara juga adalah tokoh Tionghoa Muslim. Tokoh Tionghoa Muslim penting
lainnya dari masa pra kolonial menurut tradisi lisan, adalah Kiai Telingsing (Tan
Ling Sing atau Ling Sing), yang merupakan mitra Sunan Kudus di kota Kudus,
Jawa Tengah, dekat dengan Demak. Orang-orang lokal Kudus tidak hanya
“menguduskan” Kiai Telingsing (disebut “Mbah Sing”) tetapi juga melanjutkan
ajarannya. Salah satu ajaran Telingsing yang diadopsi masyarakat setempat adalah
solat sacolo saloho dongo sampurno (salat sebagai doa sempurna).138
Menurut Opan dalam tradisi lisan Cirebon ada nama Syekh Quro alias Syekh
Mursyahadatillah atau Syekh Hasanuddin. Syekh Quro datang ke Cirebon bersama
rombongan Cheng Ho. Ia adalah putera seorang ulama besar dari Champa yang
bernama Syekh Yusuf Siddik. Pada awalnya Syekh Quro berdakwah di Cirebon,
namun karena mendapat hambatan dari penguasa, akhirnya ia pergi dan
melanjutkan dakwahnya di Kerawang. Di tempat baru ini Syekh Quro membangun
sebuah pondok sebagai tempat dakwah dan penyiaran agama Islam. Bahkan, Nyai
Subang Larangistreri Prabu Siliwangi yang juga nenek Sunan Gunung
134
Al Qurtuby, “The Imprint…, h. 171-186. 135
S. AI Qurtuby, “The Tao of Islam: Cheng Ho and the Legacy of Chinese Muslims in
Pre-Modern Java”. Studia Islamika, vol. 15, no. 1, 2009, h. 51-78. 136
Babah Liem adalah seorang Tionghoa Muslim, duta besar Tiongkok untuk Demak,
dan pemimpin Nan Lung (Naga Selatan), sebuah serikat pekerja Tionghoa di luar negeri
yang berbasis di Jawa yang berfungsi sebagai organisasi sosial untuk melestarikan warisan
dan budaya Tionghoa. Asosiasi Tionghoa perantauan ini didirikan oleh komunitas Tionghoa
lokal yang berada di Jawa setelah ekspedisi Cheng Ho. 137
Sultan Hadlirin adalah seorang Tionghoa Muslim yang nama aslinya adalah Wintang
(batu nisannya terletak di dekat Masjid Mantingan Jepara). Diceritakan bahwa Wintang
masuk Islam oleh Sunan Kudus, salah satu orang suci Muslim Jawa yang terkenal, ditemani
oleh Rakim, seorang Tionghoa Muslim lainnya. Sejak saat itu namanya berubah menjadi
Hadlirin yang berarti “kedatangan”. Lihat Amen Budiman, Masyarakat Islam Tionghoa di
Indonesia, (Semarang, Tanjung Sari, 1979). 138
Al Qurtuby, “The Imprint…, h. 171-186.
60
Jatipernah menuntut ilmu di bawah asuhan Syekh Quro.139
Ia memiliki anak yang
bernama Tan Go Hoat alias Syekh Bentong. Ialah yang pertama kali membuat
bedug yang sekarang disimpan di masjid Gunung Jati.140
Selain itu, dikenal juga
nama Haji Kung Wu Ping yang merupakan anak buah Cheng Ho yang kemudian
mendirikan pemukiman Tionghoa Muslim Hanafi di Sarindil, Talang dan Sembung.
Kemudian Haji Tan Eng Hoat alias Maulana Ifdhil Hanafi alias Pangeran Adipati
Wirasanjaya mengembangkan pemukiman Tionghoa Muslim tersebut. Haji Tan Eng
Hoat ini kemudian membantu Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan dan
mengembangkan Islam di wilayah Priangan Timur sampai ke Garut. Haji Tan Eng
Hoat kemudian menjadi Raja Muda bawahan Kerajaan Cirebon yang berkedudukan
di Kadipaten. Ponakannya yang bernama Tan Sam Cai (Muhammad Syafi‟I alias
Tumenggung Aria Dwipa Cula juga punya peran penting dalam Kesultanan)
sebagai Menteri Keuangan di Kesultanan Cirebon dan arsitek Kelenteng Talang,
bahkan ada juga yang mengatakan ia merupakan arsitek Guha Sunyaragi. Selain itu
juga dikenal nama Haji Kung Sem Pak alias Haji Muhammad Nurjani, keturunan
Haji Kung Wu Ping, yang mendirikan mercusuar terkenal di Cirebon.141
Munculnya
orang Tionghoa di Cirebon terkait dengan ekspedisi Cheng Ho bisa ditemukan di
Carita Purwaka Caruban Nagari. Dalam teks ini, dinyatakan bahwa pelabuhan
pertama Cirebon terletak di Pasambangan antara Gunung Sembung dan Amparan
Jati. Syahbandar (kepala pelabuhan) adalah Ki Gendeng Djumadjan Djati.142
Carita Purwaka Caruban Nagari juga menyebutkan bahwa Wei Ping (Kung
Wu Ping) dan Te Ho, bersama para pengikutnya, dalam perjalanan ke Majapahit,
mendarat di pelabuhan dan tinggal di sana selama tujuh hari.143
Selama mereka
tinggal, mereka membangun Mercusuar.144
Tjandrasasmita mengidentifikasi nama
“Te Ho” sebagai Laksamana Cheng Ho yang ditemani oleh Ma Huan dan Feh Tsin
(Fei Xin), mengunjungi Cirebon, berdasarkan laporan Ying-yai Sheng-lan oleh Ma
Huan.145
Tionghoa Muslim lainnya yang dikenal dalam tradisi lokal Cirebon adalah
Syeikh Bentong (Babah Bantong), putrinya bernama Ratna Subanci, menikah
dengan Raja Bravijaya V dari Majapahit. Dari pernikahan tersebut lahir seorang
putra bernama Jin Bun yang kemudian menjadi pendiri Kesultanan Demak dengan
gelar Raden Patah. Cerita itu juga dipertegas didalam Cerita Purwaka Caruban
139
Atja, Cerita Purwaka…, h. 31. 140
Wawancara dengan Opan Safari (Filolog dan Budayawan Cirebon) pada tanggal 19
Juli 2020. 141
H. J. de Graaf & Th. G. Th. Pigeaud, Chinese Muslims in Java in the 15th and 16th
Centuries. Edited by M. C. Ricklefs, (Melbourne: Monash University, 1984).; Atja, Cerita
Purwaka…, h. 31. 142
Atja, Cerita Purwaka…, h. 30-31. 143
Menurut Permadi, data ini diperkuat oleh pernyataan Wan Ming (Direktur Riset
Tiongkok) yang menyatakan bahwa di dalam Ying-yai Sheng-Ian juga ditulis bahwa Cheng
Ho dan pasukannya mendarat di pantai utara pulau Jawa sebelum Semarang, yaitu Moro
(Muara Jati), Sarindil dan Talang. Ketiga desa tersebut ada di Cirebon. Wawancara dengan
Permadi (Tokoh masyarakat Tionghoa) pada tanggal 26 September 2019. 144
Atja, Cerita Purwaka…, h. 31. 145
Uka Tjandrasasmita, Arkeologi Islam Nusantara, (Jakarta: Kepustakaan Populer
Gramedia. 2009), h. 92.
61
Nagari bahwa Raden Patah adalah putera Prabu Brawijaya Kertabumi dari seorang
puteri Tiongkok. Pada waktu puteri itu hamil, ia diserahkan kepada Arya Damar,
Bupati Palembang yang saat itu merupakan bawahan Majapahit. Di Palembang,
puteri itu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Jinbun. Sementara
dari Arya Damar, puteri itu mempunyai anak yang diberi nama Raden Kusen.
Setelah remaja, Jinbun alias Raden Patah dan Raden Kusen berangkat ke Majapahit.
Raden Kusen diangkat menjadi Bupati Teterung, sedangkan Raden Patah diangkat
menjadi Adipati Bintoro di Demak. Raden patah dengan dukungan para wali dan
penguasa kota-kota pantai utara dan beberapa kota seberang laut, akhirnya berhasil
meruntuhkan Majapahit, dan karena itu ia dinobatkan menjadi Sultan Demak yang
pertama dengan gelar Sultan Akbar al-Pathah.146
Dalam konteks Cirebon, salah satu yang paling terkenal di kalangan Tionghoa
Muslim Cirebon adalah Putri Ong Tien147
(istri Sunan Gunung Jati). Putri Ong Tien
telah menjadi simbol budaya penduduk lokal, baik Tionghoa maupun non
Tionghoa, dan berfungsi sebagai figur pemersatu antara kedua kelompok di
Cirebon. Salah satu yang dapat dilihat dari makam Putri Ong Tien, yakni hingga
saat ini banyak dikunjungi orang dari berbagai latar belakang etnis dan agama di
seluruh Indonesia, bahkan manca negara.
Dengan demikian, menurut penulis penting untuk mengetahui bahwa
keberadaan Tionghoa Muslim dalam fase awal islamisasi Jawa tidak hanya
diungkapkan oleh kisah dan laporan para penjelajah asing dan sumber-sumber
Tiongkok, tetapi juga dalam kronik, sejarah, dan tradisi lisan Jawa lokal. Sejumlah
artefak Islam, peninggalan arkeologis, dan warisan budaya yang menunjukkan
pengaruh orang Tionghoa juga membuktikannya. Karena itu, kita dapat
mengasumsikan pengembangan semacam budaya Tionghoa-Jawa atau Muslim
sebagai hasil penggabungan budaya Tionghoa-Islam-Jawa.
C. Pra Kolonial: Muslim Tionghoa sebagai Budaya Hibrida
Penulis dalam bagian ini ingin memulai dengan mengatakan bahwa Tionghoa
Muslim bukanlah orang baru di Indonesia. Ada beberapa bukti keberadaan
Tionghoa Muslim di Jawa sejak abad ke-15 dan keterlibatan mereka dalam dakwah
Islam sejak saat itu.148
Lombard dan Salmon mengatakan interaksi budaya Tionghoa
dan lokal pada waktu itu tercermin dalam arsitektur masjid. Disebut sebagai sub
kultur Muslim peranakan, mereka melihat interaksi seperti itu sebagai bentuk
“persatuan suci” kosmopolitan, yang menggabungkan kontribusi positif dari
ideologi Islam dan teknik Tiongkok.149
146
Atja, Cerita Purwaka…, h. 93-94. 147
Atja, Cerita Purwaka…, h. 40-41. 148
S. Al Qurtuby, Arus Cina-Islam-Jawa: Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa
dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV&XVI, (Yogyakarta: Inspeal
Ahimsya Karya Press, 2003).; M. Ali, “Chinese Muslims in Colonial and Postcolonial
Indonesia”. Explorations, vol. 7, no. 2, 2007, h. 1-22. 149
D. Lombard & C. Salmon, “Islam and Chineseness”. In A. Gordon (ed.), The
Propagation of Islam in the Indonesian-Malay Archipelago, (Kuala Lumpur: Malaysian
Sociological Research Institute, 2001), h. 181-208.
62
Ada beberapa teks sejarah yang menyebutkan keberadaan Tionghoa Muslim di
Indonesia sebelum masa kolonial Belanda. Seorang Tionghoa Muslim, Ma Huan,
yang menemani Laksamana Cheng Ho dalam serangkaian ekspedisinya ke Laut
Selatan (1405-1433), melaporkan dalam bukunya Ying-yai Sheng-Ian: The Overall
Survey of the Ocean's Shores (1433),150
bahwa sudah ada etnis Tionghoa di Jawa
pada waktu itu dan beberapa dari mereka adalah Muslim. Memang laporan tersebut
tidak menyebutkan tentang pemberitaan Islam oleh Cheng Ho pada waktu itu.
Namun, dengan menggunakan sejarah lokal dan sumber-sumber lain, di antaranya
karya Yuanzhi,151
Sen,152
dan Budiman,153
mereka berpendapat bahwa Cheng Ho
dan para pengikutnya telah menyebarkan Islam secara langsung atau tidak langsung
di Jawa.
Selain beberapa sumber lokal di atas, ada juga diketemukan karya
kontroversial, The Malay Annals of Semarang and Cerbon, sering dikutip untuk
mendukung peran Tionghoa Muslim menyebarkan Islam di Jawa. Ini bukan
merupakan teks lontar awal, tetapi ditemukan pertama kali dalam karya
Parlindungan154
sebagai lampiran dari bukunya yang berbahasa Melayu tentang
legenda di Sumatera, berjudul Pongkinangolngolan Sinambela gelar Tuanku Rao:
Teror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak 1816-1833.155
Lampiran buku
tersebut membahas peranan etnis Tionghoa Muslim bermazhab Hanafi dalam
perkembangan agama Islam di Pulau Jawa, 1411-1564. Teks tersebut kemudian
direproduksi, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dikomentari dalam sebuah
buku oleh Graaf dan Pigeaud.156
Ricklefs yang mengedit buku tersebut, meskipun
mengakui upaya dari kedua penulis, mempertanyakan keaslian Sejarah Melayu.
150
Ma Huan, Ying-yai Sheng-Ian: The Overall Survey of the Ocean's Shores
(1433).Translated by J. V. G. Mills. Edited by Feng Ch‟eng Chun, (Cambridge: The
University Press for the Hakluyt Society, 1970). 151
Kong Yuanzhi, Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah di
Nusantara, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2007), h. 60-61. 152
T. T. Sen, Cheng Ho and Islam in Southeast Asia, (Singapore: Institute of Southeast
Asian Studies, 2009). 153
A. Budiman, Masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia, (Semarang: Tanjung Sari,
1979). 154
Menurut Parlindungan, ia menerima teks yang disebut Sejarah Melayu Semarang
dan Cerbon dari seorang administrator Belanda bernama Poortman, yang meninggal di
Voorburg, Belanda tahun 1951. Poortman mengatakan bahwa catatan sejarah itu ditemukan
di kuil-kuil di Semarang dan Cirebon. Begitulah klaim Parlindungan. Namun, upaya serius
dari para sarjana Belanda untuk mengidentifikasi orang ini, tidak menghasilkan apa-apa,
Oleh karena itu, Ricklefs bertanya-tanya apakah Poortman ini mungkin bukan hanya
makhluk atau imajinasi Parlindungan, atau mungkin imajinasi yang rumit. 155
M. O. Parlindungan, Pongkinangolngolan Sinambela gelar Tuanku Rao: Terror
Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak 1816-1833, (Djakarta: Tandjung
Pengharapan, 1964). Lihat M. O. Parlindungan, Pongkinangolngolan Sinambela gelar
Tuanku Rao: Terror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak 1816-
1833, (Yogyakarta: LKiS, 2007). 156
H. J. de Graaf & Th. G. Th. Pigeaud, Chinese Muslims in Java in the 15th and 16th
Centuries. Edited by M. C. Ricklefs, (Melbourne: Monash University, 1984).
63
Bahkan, Lombard157
juga meragukan keberadaannya, dan karenanya menolak
gagasan bahwa sebagian besar Wali adalah Tionghoa peranakan. Sementara Berg
mengatakan sebagian besar Wali adalah keturunan Arab Hadrami.158
Terlepas dari perdebatan di atas, menurut penulis, beberapa teks sejarah
tersebut masih dapat digunakan sepanjang dalam usaha mendapatkan beberapa
pandangan terkait dengan konteks pembahasan. Jika ditelusuri lagi, bukan hanya itu
tatapi teks-teks sejarah lokal lainnya seperti Serat Kanda dan Babad Tanah Jawi,
Muljana, dalam bukunya yang kontroversial berjudul Runtuhnya Negara Hindu-
Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara159
mengatakan bahwa
Tionghoa Muslim berperan penting dalam pendirian kerajaan Islam di Jawa, dan
beberapa orang Muslim yang taat beragama di Jawa yakni Wali Songoberasal
dari Tiongkok.160
Teks Jawa kontroversial lainnya, disebut Serat Dermagandul,
juga menganggap beberapa Wali Songo berasal dari Tiongkok.161
Meskipun
keabsahan catatan-catatan lokal ini harus diteliti lebih jauh lagi, namun, menurut
penulis, catatan-catatan tersebut tidak boleh diabaikan karena merupakan bagian
dari ingatan kolektif masyarakat, yang penting dalam memberikan petunjuk tentang
hubungan antara Tionghoa dan Muslim di masa lalu.
Beberapa hal terkait dengan Tionghoa Muslim di Nusantara atau lebih sepsifik
Indonesia juga banyak dikaji oleh Al Qurtuby dalam beberapa karyanya, Arus Cina-
Islam-Jawa: Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Agama
Islam di Nusantara Abad XV&XVI,162
“The Tao of Islam: Cheng Ho and the Legacy
of Chinese Muslims in Pre-Modern Java”;163
“The Imprint of Zheng He and
Chinese Muslims in Indonesia‟s Past”;164
“Islam di Tiongkok dan Cina Muslim di
Jawa pada Masa Pra-Kolonial Belanda”,165
telah berusaha mengumpulkan lebih
banyak sumber untuk mendukung kasus kontribusi Tionghoa Muslim dalam
lslamisasi. Menurutnya, keberadaan Tionghoa Muslim dalam penyebaran awal
Islam tidak hanya dibuktikan oleh para sarjana Barat, sumber-sumber Tionghoa,
teks-teks Jawa lokal dan tradisi lisan seperti dibahas di atas, tetapi juga oleh
157
D. Lombard, “H. J. de Graaf & Th. G. Th. Pigeaud, Chinese Muslims in Java in the
15th and 16th Centuries”. Archipel, vol. 32, no. 1, 1986, h. 186-187. 158
L. W. C. Van den Berg, Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara, (Jakarta: INIS,
1989). 159
Buku ini adalah salah satu buku yang kontroversial dari Slamet Muljana, diterbitkan
pada tahun 1968, dan ditarik dari peredaran pada tahun 1971 oleh pihak berwenang
Indonesia, tetapi baru-baru ini diterbitkan ulang di Yogyakarta oleh Lembaga Kajian Islam
dan Sosial pada tahun 2005. 160
S. Muljana, Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam
di Nusantara, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005). 161
Ali, “Chinese Muslims…, h. 1-22. 162
S. Al Qurtuby, Arus Cina-Islam-Jawa: Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa
dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV&XVI, (Yogyakarta: Inspeal
Ahimsya Karya Press, 2003). 163
AI Qurtuby, “The Tao of Islam…, h. 51-78. 164
Al Qurtuby, “The Imprint…, h. 171-186. 165
S. Al Qurtuby, “Islam di Tiongkok dan China Muslim di Jawa Pada Masa Pra-
Kolonial Belanda”. Konfrontasi, vol. 1, no. 2, 2012, h. 69-90.
64
pengaruh Tionghoa pada desain arsitektur masjid dan makam tua di Jawa, seperti
makam Sunan Giri di Gresik, desain istana Cirebon dan arsitektur masjid Demak di
Jawa Tengah. Dua contoh terkait di Jakarta adalah mesjid Angke dan masjid Kebon
Jeruk. Masjid Angke memiliki beberapa ornamen Tionghoa di gerbang dan tali
seperti yang ada di kuil Tionghoa; sementara ada batu nisan Muslim di Masjid
Kebon Jeruk yang memiliki aksara Tiongkok dan Arab. Berangkat dari beberapa
sumber sejarah dan situs keagamaan tersebut, Al Qurtuby berpendapat bahwa ada
budaya Tionghoa Muslim-Jawa di seluruh Jawa, sebagai hasil dari interaksi antara
Cheng Ho dan Tionghoa Muslim lainnya dengan orang lokal Jawa.
Selain Al Qurtuby, Yuanzhi telah mencatat bahwa beberapa situs keagamaan
Tionghoa mungkin memiliki hubungan dengan Laksamana Cheng Ho, seperti Kuil
Ancol di Jakarta dan Sam Po Kong (Kuil Cheng Ho, juga dikenal sebagai Gedung
Batu) di Semarang. Merujuk karya Tanggok bahwa beberapa orang bahkan
mengatakan kuil seperti itu pernah berfungsi sebagai masjid.166
Selain itu, kontak
budaya antara Tionghoa dan Indonesia, serta perkembangan Islam di Tiongkok
selama abad 13 dan 15 digambarkan oleh Sen untuk mendukung klaimnya tentang
hubungan dekat antara ekspedisi Cheng Ho dan Islam di Asia Tenggara.167
Penulis
melihat semua sumber yang ada mecoba meyakinkan kita semua bahwa ada
interaksi antara Tionghoa dan Islam di Indonesia, khususnya Jawa di masa lalu
sekalipun sumber-sumber tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan peranan
Tionghoa Muslim dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan kata lain, semua
literatur tersebut, sampai batas tertentu, mungkin telah melebih-lebihkan pengaruh
Tionghoa terhadap perkembangan Islam di Jawa, atau memang seperti itu adanya.
Sebelum kedatangan Belanda, ada banyak juga orang Tionghoa yang masuk
Islam. Hal tersebut menurut Giap dilakukan sebagai cara mengintegrasikan diri
mereka ke dalam masyarakat Jawa, dengan menikahi penduduk setempat dan
mengadopsi nama-nama Jawa sehingga dapat meningkatkan derajat sosial dan
politik mereka, juga tidak biasa bagi mereka untuk berasimilasi dengan kelompok
mayoritas lokal. Namun, dengan perkembangan politik yang menyertai
kolonialisme Belanda, bentuk interaksi budaya antara Tionghoa dan Muslim ini
menurun. Oleh karena itu, generasi Tionghoa Muslim di masa yang akan datang
sulit dilacak karena sebagian besar dari mereka akhirnya berasimilasi, dan ada
kehancuran budaya Tionghoa Muslim-Jawa. Keadaan tersebut disebabkan oleh
beberapa hal, termasuk meningkatnya kekuatan rezim kolonial Belanda, perubahan
politik di Tiongkok, pergantian Islam yang lebih ortodoks, dan meningkatnya
kedatangan perempuan Tionghoa dan kebangkitan nasionalisme Tionghoa.
Hancurnya budaya Tionghoa Muslim-Jawa berarti bahwa etnis Tionghoa pada
waktu itu sebagian besar non Muslim dan dianggap oleh beberapa orang Indonesia
166
M. I. Tanggok, “The Role of Chinese Communities lo the Spread of Islam in
Indonesia”. Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, vol. 7, no. 3, 2006, h. 249-262. 167
T. T. Sen, Cheng Ho and Islam in Southeast Asia, (Singapore: Institute of Southeast
Asian Studies, 2009).
65
asli sebagai “orang lain” yang signifikan dan “orang asing” yang tidak
berasimilasi.168
D. Era Kolonial Belanda: Kemunduran Budaya Muslim Tionghoa-Jawa
Kebijakan pemisahan dari pemerintahan Belanda menyebabkan penarikan
batas yang lebih ketat antara orang Tionghoa dan pribumi (Indonesia), serta
mengurangi jumlah konversi etnis Tionghoa ke Islam. Benedict Anderson
sebagaimana dikutip Ang berpendapat bahwa itu adalah kebijakan kolonial Belanda
yang secara artifisial menciptakan “minoritas Tionghoa” di Hindia Belanda saat
itu.169
Dalam status sipil, Belanda menciptakan tiga kategori rasial, masing-masing
dengan hak dan hak hukum yang berbedaorang Eropa berada di level paling atas,
orang-orang asingterutama Tionghoa, juga orang Arab dan India berada di level
menengah, sedangkan penduduk pribumi (Indonesia) menempati posisi paling
bawah. Status istimewa ini memberi kesan pada etnis Tionghoa bahwa status sosial
orang pribumi Indonesia lebih rendah. Karena Islam umumnya dikaitkan dengan
orang pribumi Indonesia, banyak etnis Tionghoa yang dianggap masuk Islam akan
menurunkan status sosial mereka.170
Pada saat yang sama, kebijakan Belanda lebih
suka menjaga etnis Tionghoa agar tidak berbaur dengan penduduk pribumi dan
masuk Islam. Sebagai hasil dari kebijakan ini, etnis Tionghoa menjadi kelas
perantara yang terutama terlibat dalam kegiatan ekonomi dan tinggal di distrik-
distrik tertentu. Pada saat yang sama, orang pribumi Indonesia semakin memegang
persepsi negatif terhadap orang Tionghoa Indonesia, seperti menjadi eksklusif dari
mayoritas orang Indonesia dan mengeksploitasi sumber daya masyarakat pribumi.
Namun, terlepas dari kebijakan kolonial Belanda, masih ada beberapa etnis
Tionghoa yang masuk Islam, terutama untuk pertimbangan keamanan dan ekonomi.
Setelah pembunuhan massal etnis Tionghoa oleh pasukan Belanda dan tentara lokal
di Jakarta pada 1740, banyak yang masuk Islam untuk menghindari menjadi korban.
Sementara yang lainnya dikonversi karena alasan ekonomi, sehingga mereka akan
dianggap “pribumi” dan karenanya dikenakan pajak yang lebih rendah. Hal ini
menyebabkan Belanda mengambil tindakan lebih lanjut untuk mencegah konversi
agama etnis Tionghoa, karena telah menghasilkan kerugian besar bagi pemerintah
kolonial.171
Lombard dan Salmon mencontohkan bahwa pada tahun 1745, orang
Tionghoa yang pindah agama dilarang berasimilasi dengan Muslim setempat dan
wajib membayar pajak yang lebih tinggi. Kolonial Belanda juga khawatir bahwa
interaksi yang erat antara etnis Tionghoa dan penduduk setempat dapat
168
T. S. Giap, “Islam and Chinese assimilation in Indonesia and Malaysia”. In Chinese
Beliefs and Practices in Southeast Asia, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1993), h. 59-
100. 169
I. Ang, “Trapped in Ambivalence Chinese Indonesians, victimhood and the Debris
of History”. In M. Morris & B. de Bary (eds.), „Race‟ Panic and the Memory of Migration,
(Hong Kong: Hong Kong University Press, 2001), h. 21-47. 170
W. G. Skinner, “Creolized Chinese Societies in Southeast Asia”. In A. Reid (ed.),
Sojourners and Settlers: Histories of Southeast Asia and the Chinese, (Sydney: Allen and
Unwin, 1996), h. 50-93. 171
Lombard & Salmon, “Islam and Chineseness”, h. 181-208.
66
mengganggu kestabilan kekuasaan mereka. Untuk memisahkan para mualaf dari
Muslim lokal, Belanda menunjuk kapitan khusus untuk memimpin Tionghoa
Muslim dan membangun sebuah masjid, yakni mesjid Krukut khusus untuk
mualaf.172
Hew dalam penelitiannya menemukan bahwa banyak pemimpin Tionghoa
Muslim menyalahkan pemerintahan kolonial Belanda karena lebih sedikit Tionghoa
yang masuk Islam. Beberapa dari mereka melihat era kolonial Belanda sebagai
periode paling gelap dalam sejarah orang Tionghoa di Indonesia pada umumnya dan
Tionghoa Muslim pada khususnya.173
Oleh karena itu, bagi para pemimpin
Tionghoa, penting untuk menekankan sejarah Tionghoa Muslim sebelum
kedatangan Belanda sebagai cara memosisikan diri di Indonesia kontemporer dan
mengajarkan Islam ke etnis Tionghoa. Dalam konteks ini, penelitian Hew secara
lebih rinci melihat bagaimana etnis Tionghoa Muslim mengutarakan kembali
ingatan bersejarah mereka. Penting juga dicatat bahwa alasan lain yang
berkontribusi terhadap penurunan konversi etnis Tionghoa ke Islam, seperti
meningkatnya ortodoksi Islam dan kebangkitan nasionalisme Tionghoa pasca abad
ke-19.174
Tumbuhnya bentuk Islam yang tegas yang menuntut umat Islam untuk
mengamalkan agama mereka dengan lebih kaku, seperti tidak makan daging babi
dan meninggalkan penyembahan dewa mungkin telah lebih jauh mengecilkan hati
orang Tionghoa Indonesia dari menjadi Muslim.175
Hubungan antara etnis Tionghoa dan Muslim lokal juga memburuk setelah
Perang Jawa (1825-1830) dan serangan Sarekat Islam (1912). Selama puncak
Perang Jawa, Diponegoro, seorang pemimpin Jawa mengambil sikap tanpa
kompromi terhadap etnis Tionghoa. Ia dikatakan telah mengeluarkan dekrit yang
memerintahkan Tionghoa di distrik-distrik tertentu untuk mengkonversi atau
menghadapi hukuman mati176
Dia juga mensyaratkan sunat segera bagi “mereka”
yang menyatakan sebagai Muslim. Sementara pada tahun 1905, Sarekat Dagang
Islam (SDI) didirikan oleh beberapa pengusaha Muslim asli untuk melindungi
kepentingan bisnis mereka dari pedagang Tionghoa yang lebih mapan. Pada tahun
1912, SDI direorganisasi dengan nama Sarekat Islam (SI). Pada tahun yang sama, ia
meluncurkan boikot terhadap pedagang Tionghoa yang berubah menjadi kerusuhan
terhadap Tionghoa dalam beberapa hari kemudian, di sekitar Surakarta dan Jawa
Tengah.177
172
Lombard & Salmon, “Islam and Chineseness”, h. 181-208. 173
W. W. Hew, “Negotiating Ethnicity and Religiosity: Chinese Muslim Identities in
Post-new Order Indonesia”, (A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy
Department of Political and Social Change School of International, Political and Strategic
Studies College of Asia and the Pacific of The Australian National University, 2011), h. 62. 174
M. Jacobsen, “Islam and Processes of Minorisation among Ethnic Chinese in
Indonesia: Oscillating between Faith and Political Economic Expediency”. Asian Ethnicity,
vol. 6, no. 2, 2005, h. 71-87. 175
Hew, “Negotiating Ethnicity…, h. 62. 176
Lombard & Salmon “Islam and Chineseness”, h. 115-131. 177
Azyumardi Azra “The Indies Chinese and the Sarekat Islam: An account of the Anti-
Chinese Riots in Colonial Indonesia”. Studia lslamika, vol. 1, no. 1, 1994, h. 25-54.; T.
67
Terlepas dari ketegangan di atas, Ali mengatakan bahwa ada cukup banyak
Tionghoa Muslim yang terlibat dalam perang anti-kolonial lokal dan gerakan
nasionalis, termasuk Johan Muhammad Chai, seorang Tionghoa Muslim yang
menandatangani Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dalam membahas religiusitas
beberapa Tionghoa Muslim, Ali juga mengatakan bahwa pada awal abad ke-20,
terdapat berbagai orientasi keagamaan di antara mereka, mulai dari sinkretik,
ortodoks hingga Islam politik. Seperti itu keberagaman dalam religiusitas
menunjukkan bahwa Tionghoa Muslim telah berintegrasi ke dalam budaya lokal
dengan berbagai cara.178
Dari berbagai peristiwa di atas memperkuat stereotip negatif di antara orang
pribumi Indonesia. Ditambah lagi banyak kasus-kasus korupsi dengan nilai yang
sangat besar banyak dilakukan oleh orang-orang Tionghoa Untuk itu, penulis
berpendapat bahwa untuk mengubah stereotif tersebut, maka memori kolektif
tentang konstruksi orang Tionghoa sebagai “orang luar” perlu ditata ulang guna
menghindari konflik yang berulang antara orang Tionghoa dan warga asli. Persepsi
masyarakat asli terhadap etnis Tionghoa dapat diubah melalui penulisan Kembali
sejarah mereka secara proporsional dan sesuai konteks. Mudah-mudahan dengan
memahami sejarah secara benar, akan dapat merekatkan Kembali hubungan
“mesra” yang dulu sempat terbina.
Shiraishi, An Age in Motion. Popular Radicalism in Java 1912-1926, (Ithaca: Cornell
University Press, 1990). 178
Ali, “Chinese Muslims…, h. 1-22.
69
BAB III
SEJARAH KESULTANAN CIREBON
Pada bab III ini penulis akan membahas tentang sejarah Kesultanan Cirebon.
Bagian ini secara husus akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya Kesultanan
Cirebon, dialektika politik di Kesultanan Cirebon dan sejarah kedatangan etnis
Tionghoa di Cirebon. Pembahasan ini menjadi penting disajikan agar kita mendapat
gambaran yang komprehensif tentang Kesultanan Cirebon dan kedatangan etnis
Tionghoa di Cirebon sebelum pembahasan tentang relasi sosial budaya antara etnis
Tionghoa dan masyarakat Cirebon di bab selanjutnya.
A. Profil dan Dialektika Kesultanan
1. Kesultanan Cirebon
Proses islamisasi di Nusantara dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya
dengan mendirikan sebuah pusat kekuataan Islam yang dilembagakan, yakni
kesultanan. Kesultanan didirikan sebagai manifestasi sosial dan politik yang
dilakukan untuk mendukung komunitas Islam yang ada di Nusantara. Dalam
konteks tersebut, sekurangnya ada beberapa fungsi kesultanan itu didirikan, di
antaranya sebagai pusat kekuatan di masa lalu, pusat kebudayaan, pusat keilmuan
dan pusat keagamaan.1
Salah satu kesultanan yang berdiri di Nusantara adalah Kesultanan Cirebon.
Kesultanan ini berdiri pada tahun 1482 M. dan menandai sebuah era baru yang ada
di wilayah Jawa Barat. Hal ini dikarenakan Cirebon sebelum itu berada di bawah
kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pendirian
Kesultanan Cirebon bukan merupakan awal dari gerakan islamisasi, tetapi pendirian
institusi politik yang dimanifestasikan sebagai Kesultanan Cirebonadalah
merupakan kelanjutan dari proses islamisasi yang sudah berlangsung dan dilakukan
oleh para pendakwah sebelum kedatangan Sunan Gunung Jati.2
Sebelum Cirebon menjadi kesultanan, daerah ini merupakan sebuah pedukuhan
kecil yang terletak di bibir atau pesisir teluk Cirebon, orang-orang menyebutnya
dengan nama Lemah Wungkuk atau disebut juga Dukuh Tegal Alang-Alang, sebab
pedukuhan ini dipimpin oleh Ki Gedeng Alang-Alang. Sikap ramah dari pribadi Ki
Gedeng Alang-Alang menjadi salah satu faktor pendorong atau menarik perhatian
para pendatang dari berbagai suku, agama, budaya dan bahasa yang berbeda.
Semuanya bisa datang, bahkan untuk menetap sekalipun. Hal tersebut sebagaimana
diceritakan dalam Purwaka Caruban Nagari, yaitu: “Wis mandeg ta sira teguh
alang-alang dukuh kang mangko sinebut Caruban tumuli, mapan janmapada
1J. Burhanudin, “Converting Belief, Connecting People: The Kingdoms and the
Dynamics of Islamization in Pre-Colonial Archipelago”. Studia Islamika, vol. 25, no. 2,
2018, h. 247-278.; S. F. Alatas, “Notes on various theories regarding the Islamization of the
Malay archipelago”. Alatas, SF (1985). Notes on Various Theories Regarding the
Islamization of the Malay Archipelago. The Muslim World, vol. 75, 1985, h. 162-175. 2T. Tendi, D. Marihandono, & A. Abdurakhman, “Between the Influence of
Customary, Dutch, and Islamic Law: Jaksa Pepitu and Their Place in Cirebon Sultanate
History”. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, vol. 57, no. 1, 2019, h. 117-142.
70
sukheng pesambangan desa keh mara ngkene pantaraning pra dol tinuku”
(akhirnya berdirilah Dukuh Tegal Alang-Alang yang kelak menjadi Caruban.
Banyak orang dari Dukuh Pesambangan yang datang ke daerah tersebut, salah
satunya mereka yang berprofesi sebagai pedagang).3
Sosok pangeran Cakrabuana (Ki Somadullah/Pangeran Walangsungsang) yang
mendirikan wilayah Lemah Wungkuk atas titah gurunya Syekh Nurjati, seorang
muballig yang pernah singgah di Pelabuhan Muara Jati. Adapun tujuan pendirian
wilayah ini adalah untuk memperluas penyebaran Islam di pesisir utara pantai Jawa
dan daerah sekitarnya.4
Ki Somadullah membangun Lemah Wungkuk atas titah gurunya dan
mengundang penduduk yang tadinya tinggal di Amparan Jati yang merupakan salah
satu jalur perdagangan internasional dan pelabuhan penting saat itu. Dalam proyek
pendirian wilayah itu tercatat ada 52 orang yang berasal dari berbagai suku bangsa
ikut membantu dan bergabung. Mereka bekerja sama dan bahu membahu
membersihkan hutan belukar. Lemah Wungkuk berkembang pesat dan menarik
banyak orang untuk kemudian datang dan menetap. Jumlah penduduk meningkat
tajam dari 52 menjadi 346 dalam waktu singkat, dengan rincian 196 orang berasal
dari suku Sunda, 106 orang suku Jawa, 16 orang dari Sumatera, 4 orang dari suku
Melayu, 2 orang dari India, 2 orang dari Persia, 3 orang dari Syam/Syiria, 11 orang
dari Arab dan 6 orang dari Tiongkok. Kemajemukan etnik dan asal-usul penduduk
menunjukkan betapa pesatnya perkembangan wilayah ini, baik dari segi demografis
maupun ekonomis.5
Ki Somadullah berhasil mengembangkan wilayah Lemah Wungkuk sehingga
mampu mengungguli wilayah Amparan Jati dimana Muara Jati menjadi pusat
pelabuhan internasional, bahkan pada perkembangannya, Amparan Jati kemudian
menjadi bagian dari wilayah Lemah Wungkuk dan pelabuhan internasional beralih
ke Lemah Wungkuk. Wilayah Lemah Wungkuk semakin hari bertambah luas
menjadikan wilayah ini berubah nama menjadi Caruban atau Cerbon atau Cirebon
yang berarti campuran.6 Jadi perubahan nama dari Lemah Wungkuk menjadi
Caruban terjadi pada masa Ki Somadullah karena penduduk yang mendiami tempat
itu berasal dari berbagai bangsa, agama dan bahasa, serta pekerjaan yang berbeda.
Cirebon tumbuh menjadi kota yang ramai, dan pantainya berkembang menjadi
pelabuhan yang ramai dengan kegiatan perdagangan melalui laut. Cirebon
berkembang menjadi pelabuhan penting di pesisir utara pulau Jawa. Ada empat
faktor yang memengaruhi Cirebon menjadi pelabuhan penting. Pertama, letak
geografisnya yang strategis. Pelabuhan Cirebon berada pada lokasi berbentuk teluk
3N. H. Lubis, Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat, (Bandung: Alqaprint, 2000), h.
45. 4Atja, Carita Purwaka Caruban Nagari: Karya Sastra sebagai Sumber Pengetahuan
Sejarah, (Bandung: Proyek Pemuseuman Jawa Barat, 1986), h. 33.; D. N. Rosyidin dan A.
Syafaah, Keragaman Budaya Cirebon: Survey atas Empat Entitas Budaya Cirebon,
(Cirebon: Elsi Pro, 2016), h. 25. 5D. N. Rosyidin, Ulama Paska Sunan Gunung Jati, Studi atas Sejarah dan Jaringan
Intelektual Cirebon Pada Abad ke 16 Hingga Abad ke 18, (Laporan penelitian, IAIN Syekh
Nurjati, 2014), h. 36-37. 6Rosyidin dan Syafaah, Keragaman Budaya Cirebon…, h. 25-26.
71
sehingga terlindung dari gelombang pasang air laut. Kedua, pelabuhan Cirebon
berada di bagian tengah pesisir utara pulau Jawa, dan cukup jauh dari pelabuhan
lain, seperti Jepara, Tuban dan Surabaya di timur pulau Jawa dan Sunda Kelapa
serta Banten di sebelah barat pulau Jawa. Ketiga, pelabuhan Cirebon mudah
didatangi dengan perahu, bahkan dapat dimasuki oleh kapal-kapal berukuran besar.
Keempat, hubungan antara pelabuhan dengan daerah pedalaman berlangsung lancer,
baik melalui sungai atau darat.7
Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang menetap di wilayah
sebagaimana disebutkan di atas, maka status pedukuhan Tegal Alang-Alang
ditingkatkan menjadi desa dengan nama pakuwon (akuwuhan), hal itu sudah sesuai
dengan struktur pemerintahan yang diatur oleh Kerajaan Pajajaran. Perubahan status
dari pedukuhan menjadi pakuwon pada akhirnya berimplikasi pada perubahan
struktur kekuasaan lokal. Atas dasar itu, maka Ki Gedeng Alang-Alang yang
sebelumnya menjadi pemimpin pedukuhan, kemudian berubah statusnya menjadi
seorang kuwu (kepala desa). Dengan bergantinya status pedukuhan menjadi
pakuwon, maka secara otomatis nama Tegal Alang-Alang berubah menjadi Caruban
Larang.8
Ki Somadullah bukanlah tokoh pertama yang mendiami Lemah Wungkuk. Ia
justru mewarisi wilayah ini dari mertuanya, Ki Danusela yang bergelar Ki Gedheng
Alang-Alang. Ki Gedeng Alang-Alang dalam konteks ini adalah sebagai kuwu
pertama dari Pakuwon Caruban Larang. Untuk mendamping kuwu yang sudah
sepuh tersebut, maka Prabu Siliwangi9 mengutus putranya dari Nyi Rara Subang
Larang yakni Pangeran Cakrabuana untuk menjadi wakil kuwu dengan gelar Ki
Cakrabuana karena ia menjabat sebagai pangraksabumi atau wakil kuwu yang
diberikan tugas khusus dalam mengurusi masalah pertanian dan pengairan.10
Sepeninggal mertuanya, Ki Somadullah resmi menjadi Kuwu.11
Pada masanya,
Lemah Wungkuk berubah nama menjadi Caruban, Cerbon atau Cirebon.
Wilayahnya semakin luas dengan masuknya wilayah Cirebon pedalaman yang
dikenal dengan Cirebon Girang. Dengan demikian, Ki Somadullah berhasil
7A. S. Hardjasaputra dan T. Haris, (ed.), Cirebon dalam Lima Zaman (Abad ke-15
Hingga Pertengahan Abad ke-20), (Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Barat, 2011), h. 27. 8Di tahun 1389, saat Cirebon masih dikenal dengan Caruban Larang, wilayahnya terdiri
atas dua daerah, yaitu Caruban Girang dan Caruban Pantai. Wilayah Caruban pantai yang
kemudian berkembang menjadi pusat negeri Cirebon, dengan Pangeran Cakrabuana sebagai
adipatinya. Lihat P. R. Abdurrahman, Cerbon, (Jakarta: Yayasan Mitra Budaya Indonesia
dan Penerbit Sinar Harapan, 1982), h. 29. 9Prabu Siliwangi menikah dengan seorang putri beragama Islam yaitu Rara Subang
Larang, anak dari Mangkubumi Singapura/Mertasinga Caruban. Dari pernikahan tersebut,
Prabu Siliwangi memiliki tiga orang anak, yakni Pangeran Walangsungsang, Ratu Mas Lara
Santang dan Pangeran Raja Sengara/Kian Santang. Lihat P. S. Sulendraningrat, Sejarah
Cirebon, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 16. 10
A. S. Hardjasaputra, Cirebon dalam Lima Zaman: Abad Ke-15 hingga Pertengahan
Abad Ke-20, (Bandung: Penerbit Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat, 2012),
h. 23. 11
Atja, Carita Purwaka Caruban…, h. 35.
72
menggabungkan wilayah Cirebon Girang dan Cirebon Larang yang tadinya
terpisah. Dengan adanya perluasan wilayah tersebut, wilayah Cirebon meliputi
sungai Cipamali di bagian Timur, Cigugur (termasuk wilayah Kuningan) di bagian
Selatan, pegunungan Kromong di bagian Barat dan Junti di sebelah Utara.12
Dalam rangka perluasan wilayah atau ekspansi kekuasannya, Pangeran
Cakrabuana mengutus anaknya Pangeran Carbon untuk mengembangkan
pemukiman kakeknya di Caruban Girang. Upaya yang dilakukan oleh Pangeran
Arya Carbon berhasil ketika Caruban Girang meningkat statusnya menjadi
Pakuwan Caruban Girang. Karena prestasinya, maka Pangeran Carbon diangkat
sebagai kuwu pertama di Caruban Girang. Selain itu, Pangeran Cakrabuana
mengajak para pendatang yang bermukim di daerah lain dari wilayah Caruban
Larang untuk sama-sama membangun serta berpartisipasi untuk mengembangkan
wilayahnya menjadi pemukiman yang ramai.13
Dengan semakin luasnya wilayah Cirebon secara otomatis juga berimplikasi
terhadap semakin beragamnya penduduk, termasuk budaya dan tradisinya. Inilah
yang kemudian menjadi landasan sejarah yang kokoh bagi berkembangnya budaya
yang heteregon di wilayah yang nantinya bernama Caruban Nagari, yaitu negeri
dimana beragam suku bangsa dan budaya serta agama hadir. Cirebon kemudian
menjadi salah satu pusat transmisi ilmu pengetahuan dan pusat perdagangan dengan
semakin ramai dan strategisnya pelabuhan Cirebon dalam jaringan pelayaran dan
perdagangan internasional dan regional. Banyaknya artefak yang ditemukan
menunjukkan kompleksitas kebudayaan dan peradaban yang pernah singgah dan
berkembang di Cirebon.14
Pangeran Cakrabuana kemudian mengajarkan banyak hal kepada masyarakat
setempat, sebagaimana masyarakat Junjang yang pada dasarnya belum memahami
teknologi pertanian. Dalam konteks ini Pangeran Cakrabuana mengajarkan mereka
cara-cara bertani, sehingga hasil panen dapat berlipat ganda. Begitu juga dengan
masyarakat Juntinyuat dan Indramyu, mereka diajarkan bagaimana cara bertenun
yang baik sehingga dapat menghasilkan tenunan serat gebong yang bagus. Inisiatif
Pangeran Cakrabuana dalam mengajarkan masyarakat selain agar masyarakat
setempat dapat memberdayakan diri dan semua potensi yang mereka miliki, juga
sebagai bagian dari misi syiar Islam yakni dalam rangka meyakinkan masyarakat
lokal untuk memeluk agama Islam.15
Pangeran Cakrabuana juga merupakan orang yang pertama kali mengajarkan
sistem pemilihan lokal secara langsung di Cirebon. Sistem pemilihan ini
diberlakukan pada setiap level pemerintahan, termasuk pada tingkatan paling bawah
12
Supratikno Rahardjo (ed), Kota Dagang Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutera,
(Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998), h. 49.; Atja, Carita Purwaka
Caruban…, h. 35. 13
D. N. Rosyidin, dkk, Kerajaan Cirebon, (Jakarta: Puslitbang Lektor Khazanah
Keagamaan Balitbang Kementrian Agama RI, 2013), h. VI. 14
Rahardjo (ed), Kota Dagang Cirebon…, h. 51.; Rosyidin dan Syafaah, Keragaman
Budaya Cirebon…, h. 26. 15
Rosyidin, Kerajaan Cirebon, h. 29.
73
yakni dalam hal memilih kuwu16
(Kepala Desa). Sistem pemilihan ini dikenal
dengan nama uwi-uwian. Sistem pemilihan ini juga yang dilakukan oleh masyarakat
penduduk pesisir Cirebon untuk memilih Pangearn Cakrabuana yang saat itu
menjabat sebagai wakil kuwu menjadi kuwu Cirebon kedua setalah Ki Gedeng
Alang-Alang wafat pada 1447 M. Pangeran Cakrabuana menjadi kuwu selama 32
tahun (1447-1479 M).17
Seiring berjalannya waktu, Cirebon mengalami perkembangan yang begitu
pesat, dan atas prestasi yang dicapai Pangeran Cakrabuana, ia kemudian diangkat
oleh Raja Pakuan Pajajaran menjadi Tumenggung dengan gelar Tumenggung Sri
Mangana. Raja Pakuan Pajajaran akhirnya mengutus Tumenggung Jayabaya untuk
memberikan petandha kaprabon. Sehingga tidak heran jika Pangeran Cakrabuana
sangat loyal kepada Raja Pakuan Pajajaran ketika menjadi vasal dan selalu
mengirimkan bulu bekti (upeti) berupa garam dan terasi.18
Pada tahun 1479 Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan kepada
ponakannya yaitu Syarif Hidayatullah. Namun, sejak tahun 1482 Syarif
Hidayatullah tidak mau lagi mengirimkan upeti kepada Pajajaran sebagaimana yang
dilakukan pamannya. Maka, sejak saat itu Cirebon menjadi kerajaan yang berdaulat
penuh dan tidak lagi menjadi bawahan Pajajaran. Jadi dalam pendirian Kesultanan
Cirebon, Wali Songo mempunyai andil yang besar, yakni dengan tampilnya Sunan
Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Awalnya Syekh Syarif Hidayatullah
berperan sebagai juru dakwah yang mempunyai tugas untuk menyebarkan ajaran
agama Islam kepada masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, dan statusnya
sebagai salah satu keponakan dari peguasa Cirebon yakni Pangeran Cakrabuana
sekaligus juga sebagai cucu Prabu Siliwangi, Syekh Syarif Hidayatullah akhirnya
diberikan amanah untuk memegang pemerintahan dari pamannya.19
Ia bergelar
Ingkang Sinuhun Sunan Jati Purba Wisesa Panetep Panataagama Awliyah
Khalifatur Rasullah Shallallahu „Aliahi Wasalam”.20
Sunan Gunung Jati dilantik
16
Para kuwu biasanya dibantu oleh beberapa pejabat dalam struktur pemerintahan
seperti, Ki Buyut (Penasehat Kuwu), Ki Kliwon (Wakil Ki Kuwu), Ki Carik/Juru Tulis
(Penanggung Jawab Administrasi), Ki Raksabumi (Penanggung Jawab Pertanian dan
Perairan), Ki Juragan Pulisi (Penanggung Jawab Keamanan dan Ketertiban), Ki Mayor
(Pembantu Raksabumi), Ki Bahu (Pembantu Umum), Ki Capgawe (Pembantu Juragan
Pulisi), Ki Bekel (Penanggung Jawab Blok), Ki Kemit (Penjaga Desa atau Pesuruh). 17
Proses pemilihan yang dilakukan secara uwi-uwian dilakukan dengan cara
menghadirkan gegeden/gegedug (calon yang akan dipilih) dari setiap Kabuyutan. Para
gegeden ini akan berdiri di depan Bale Desa, kemudian rakyat memilih langsung dengan
cara berjongkok di depan calon pemimpinnya. Gegeden yang memiliki pemilih paling
banyak itulah yang berhak untuk menjadi kuwu di desa atau dukuh tersebut. Lihat
Hardjasaputra, Cirebon dalam Lima…, h. 47. 18
E. S. Ekajati, Sejarah Kuningan: Dari Masa Prasejarah sampai Terbentuknya
Kabupaten, (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2003), h. 13. 19
Atja, Carita Purwaka Caruban …, h. 37. 20
A. O. Safari, “Perta Naskah Cirebon”, Makalah Disampaikan dalam Forum Diskusi
Bulanan, Pusat Kajian Sejarah dan Budaya (PKSB) Jurusan Adab STAIN Cirebon, 7 Maret
2009.
74
oleh Raden Ali Rokhmatullah dan juga merupakan Ketua Dewan Wali Sango. Pada
masanya, Cirebon sebagai sebuah kekuatan politik mencapai puncaknya.
Demi memperlancar kegiatan pemerintahan, Kesultanan Cirebon membangun
Keraton Pakungwati.21
Dalam perkembangannya, keraton ini mengalami beberapa
perubahan, yakni pada tahap pertama tahun 1452, di keraton hanya terdapat
bangunan Dalem Agung Pakungwati. Bangunan ini mempunyai kesamaan struktur,
mengunakan susunan bata merah dengan ornamen wadasan setiap sisinya. Pada
bagian tengah merupakan bangunan yang terbuka, berdiri beberapa tiang tanpa
menggunakan dinding, dan di setiap tiangnya memiliki pondasi berbentuk lesung
tanpa adanya ornamen. Tiang penyanggah terbuat dari kayu dengan pondasi umpak,
sedangkan pada pangkalnya ada ukiran dan motif. Sementara di bagian atap
bangunan berbentuk atap bertipe malang semirang dengan genteng sebagai
penutupnya.22
Kemudian, pada tahap kedua tahun 1489 mulai didirikan Mesjid Agung Sang
Cipta Rasa.23
Diikuti dengan beberapa pembangunan lainnya seperti Siti Inggil,
museum benda kuno, kuncung dan kutagara wadasan, pengukuran, dan pintu buk
bacem. Pembangunan Keraton Cirebon tahap kedua juga diikuti dengan perbaikan
pada bagian lainnya seperti bangunan Siti Inggil dikelilingi dengan tembok merah
dengan adanya pasangan piring keramik yang mengadopsi budaya dari Tiongkok
dan pintu masuk berupa candi Bentar. Siti Inggil juga terdiri dari lima buah
bangunan beratapkan sirap yang berderet dari barat ke timur. Selain itu juga Mande
Malang Semirang (Mande Jajar) mempunyai tiang enam buah melambangkan
rukun iman dan seluruhnya ada 20 tiang melambangkan sifat ketuhanan.24
Tiang-
tiangnya memiliki banyak ornamen seperti pada bagian bawah pondasi berbentuk
lesung dengan ukiran flora yang berupa motif keliangan dan kangkungan dari
ragam hias Jawa Barat.
Pada bangunan museum kuno terdapat beberapa karakteristik yang berbeda
dengan bangunan yang ada pada Siti Inggil. Pada bangunan ini digunakan tembok
bata yang tertutup sampai ke atap, sedangkan ornamen-ornamen yang digunakan
tidak banyak, hanya berupa list yang terdapat pada pintu masuk dan bawahnya
berukir wadasan yang melambangkan manusia harus hidup mempunyai pondasi
yang kuat. Sementara pada pintu buk bacem digunakan bingkai gapura seperti
tampak mengadopsi kebudayaan Gujarat yaitu berupa lengkungan, juga terdapat
21
Keraton Pakungwati sejak awal telah dibangun oleh Pangeran Cakrabuana. Terhitung
setelah kematian kakeknya, yaitu Mertasinga, Pangeran Cakrabuana tidak meneruskan
kedudukannya sebagai raja. seluruh harta warisan yang diperolehnya digunakan untuk
membangun Keraton Pakungwati. Lihat H. A. Dasuki (ed.), Sejarah Indramayu,
(Indramayu: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu,1978), h. 24. 22
Dini Rosmalia, “Pola Ruang Lanskap Keraton Kasepuhan Cirebon”. Prosiding
Semarnusa IPLBI ITS Surabaya, 2018, h. 074-082.; Atja, Carita Purwaka Caruban…, h.
35.; Hardjasaputra, Cirebon dalam Lima…, h. 50-51. 23
P. S. Sulendraningrat, Babad Tanah Sunda/Babad Cirebon, (1984), h. 56-57.;
Mudhofar Muffid, dkk, “Konsep Arsitektur Jawa dan Sunda pada Masjid Agung Sang Cipta
Rasa Cirebon”. Modul , vol. 14, no. 2, 2014, h. 65-70. 24
Hardjasaputra, Cirebon dalam Lima…, h. 65-66.
75
tempelan piring keramik dari kebudayaan Tionghoa untuk memperindah tampilan
pintu buk bacem.
Pada tahap ketiga, ada beberapa perkembangan tahun 1529 ditambahkan
beberapa panambahan bangunan seperti Bale Kambang, Bangsal Agung, Dalem
Arum Kedalem, Bangunan Kaputren beserta Paseban Kaputren, Bangsal
Pringgadani, dan Jinem Pangrawitserta, juga Taman Bunderan Dewandaru dan
seterusnya.25
2. Dialektika Politik dan Islam
Rintisan pendirian Kesultanan Cirebon sudah dilakukan oleh Pangeran
Cakrabuana. Ia mulai merintis dari mulai kuwu sampai menjadi Tumenggung.
Perintisan diawali ketika ia menggantikan Ki Gedeng Alang-Alang yang wafat.
Maka, dilakukanlah proses uwi-uwian sehingga Pangeran Cakrabuana terpilih
menjadi kuwu di Caruban Nagari. Banyak proses yang dilalui dan prestasi yang
dicapai Pangeran Cakrabuana untuk menjadi Tumenggung seperti pengukuhan
kuwu-kuwu yang ada di bawah kekuasaan Caruban Larang dan membuka wilayah-
wilayah baru serta meletakkan konsep pemerintahan sehingga dapat berjalan dengan
baik.26
Pada lain kesempatan, Pangeran Walangsungsang akan berguru kepada Syekh
Maulana Maghribi, akan tetapi ia menolak dan menyarankan untuk berguru kepada
Syekh Datuk Kahfi (Syekh Maulana Idhofi). Syekh Maghribi mengatakan bahwa
ketika Pangeran Walangsungsang dan Nyi Mas Ratu Rara Santang menunaikan
ibadah haji maka ia akan dinikahi oleh Sultan Mesir kemudian dari hasil
pernikahan akan lahir pemimpin para wali di Pulau Jawa.27
Akhirnya, Pangeran
Walangsungsang dan Nyi Mas Ratu Rara Santang28
mengikuti anjuran Syekh
Maulana Maghribi untuk berguru kepada Syekh Datuk Kahfi pada tahun 1442 M.
Ketika kedatangan mereka, Syekh Datuk Kahfi merasa senang. Keduanya
diperkenankan untuk tinggal di sekitar Gunung Jati dan melarang mereka untuk
pulang ke Kerajaan Pajajaran. Syekh Datuk Kahfi juga mengatakan bahwa Nyi Mas
Ratu Rara Santang akan dipersunting oleh sultan dari Bani Israil, dan dari
perkawinan tersebut akan lahir sosok anak yang dapat mengislamkan Pulau Jawa.
Maka, tidak lama kemudian mereka berdua diperintahkan untuk menunaikan ibadah
haji ke Mekah.29
25
Hardjasaputra, Cirebon dalam Lima…, h. 67. 26
Atja, Carita Purwaka Caruban…, h. 35. 27
Ki Kampah, Babad Cirebon Carub Kandha Naskah Tangkil, (Cirebon: Rumah
Budaya Nusantara Pesambangan Jati Cirebon, 2013), h. 223-224. 28
Sejak awal, setelah Pangeran Walangsungsang dan Nyi Mas Ratu Rara Santang
dewasa, mereka berniat masuk agama Islam, akan tetapi niat itu tidak disetujui, dan
pangeran Walangsungsang beserta istrinya Indhang Ayu serta Nyi Mas Ratu Rara Santang
pergi keluar istana untuk belajar dan mendalami Islam. Mereka berguru pada Syekh Datuk
Kahfi di Amparan Jati. Selanjutnya, atas saran gurunya mereka membuka dusun baru di
kebon pesisir yang terletak dekat tepi laut di selatan Amparan Jati. Lihat Sulendraningrat,
Sejarah Cirebon, h. 18. 29
Hardjasaputra dan Haris, Cirebon dalam Lima…, h. 46-47.; Atja, Carita Purwaka
Caruban…, h. 33.
76
Setelah pulang haji dari tanah suci Mekah, Nyi Mas Ratu Rara Santang
berganti nama menjadi Hajjah Syarifah Mudaim, dan Pangeran Walangsungsang
menjadi Haji Abdullah Iman. Pada saat melakukan ibadah haji itulah Nyi Mas Ratu
Rara Santang bertemu dengan Maulana Sultan Mahmud (Syarif Abdullah) yang
memerintah kota Ismailiyah, Palestina. Ia baru saja ditinggal mati oleh istrinya dan
bermaksud menikahi Nyi Mas Ratu Rara Santang. Maka, dilamarlah Nyi Mas Ratu
Rara Santang oleh Syarif Abdullah.30
Pada akhirnya, Nyi Mas Ratu Rara Santang menikah dengan Sultan Syarif
Abdullah. Pernikahan tersebut kemudian melahirkan seorang anak yang diberi nama
Syarif Hidayat yang merupakan salah satu Wali Songo yang berjasa menyebarkan
Islam khususnya di daerah Sunda.31
Para keturunannya kelak menjadi pemimpin
agama di Pulau Jawa. Sementara Syekh Datuk Kahfi,32
Syekh Quro,33
dan Syekh
Maulana Maghribi34
merupakan utusan-utusan dakwah dari berbagai daerah, untuk
menyebarkan ajaran agama Islam di luar Jazirah Arab termasuk di Pulau Jawa.
Pada tahun 1448, ketika sedang melakukan ibadah haji, Syarifah Mudaim
melahirkan Syarif Hidayatullah di Mekah. Syarif Hidayatullah kemudian dibesarkan
di Mesir, di tempat ayahnya berada. Syarif Hidayatullah tumbuh dan berkembang
menjadi pemuda yang tangguh dan cerdas serta taat menjalankan perintah agama
Islam, bahkan ia bercita-cita untuk menyebarkan ajaran agama Islam.35
Syarif Hidayatullah mempunyai semangat yang membara untuk belajar agama
Islam, hal itu disampaikan kepada ibunya, bahkan ia berkeinginan besar untuk
berguru kepada Nabi Muhammad SAW., namun ibunya memberikan pengertian
bahwa Nabi Muhmamad SAW sudah wafat. Maka, Syarif Hidayatullah berangkat
ke Mekah dan berguru kepada Syekh Tajuddin al-Kubri. Ia belajar tentang adab
guru, zikir, dan silsilah serta beberapa ilmu agama Islam lainnya seperti ilmu
30
Sulendraningrat, Babad Tanah Sunda…, h. 17-19.; Atja, Carita Purwaka
Caruban…, h. 33. 31
Atja, Carita Purwaka Caruban…, h. 33-34. 32
Syekh Datuk Kahfi atau disebut juga Syekh Nurjati merupakan utusan dari Persia. 33
Syekh Quro adalah seorang ulama dari Campa. Ayahnya bernama Syekh Yusuf
Siddik, seorang ulama besar di Campa, yang masih ada garis keturunan dari Syekh
Jamaludin dan Syekh Jalaludin (ulama besar Mekah). Literatur lain bahkan mengatakan
bahwa Syekh Quro masih memiliki garis keturunan yang sampai pada Sayidina Husein bin
Sayidina Ali r.a dan Siti Fatimah. Syekh Quro menikah dengan Ratna Sondari (Putri Ki
Gedeng Karawang). Dari pernikahannya lahir Syekh Ahmad (Penghulu pertama di
Karawang). Cucu Syekh Ahmad dari putrinya yang bernama Nyi Mas Kedaton yakni
Musanudin yang kelak menjadi Lebe Cirebon dan memimpin Tajug Sang Cipta Rasa pada
masa Sunan Gunung Jati. Lihat Syamsurizal, dkk., Ikhtisar Sejarah Singkat Syekh
Quratul‟ain, (Karawang: Mahdita, 2009), h. 10. 34
Syekh Maulana Maghribi (w. 12 Rabiul Awwal 822 H/8 April 1419) merupakan
utusan dari Maroko. Lihat M. Fauzan, “Selubung Historiografi Syekh Maulana Maghribi,
Wonobodro”. Jurnal Penelitian, vol. 12, no. 2, 2015, h. 261-281. 35
Musyrifah Sunanto, “Syarif Hidayatullah Seorang Wali Penyebar Islam di Jawa
Barat”, (Disertasi PPS. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999), h. 33.; Atja, Carita
Purwaka Caruban…, h. 34.
77
tarekat, hakekat dan makrifat. Pasca belajar di Mekah, ia kemudian pulang ke
negara ayahnya. Ketika ia pulang, ayahnya meninggal dunia, dan ia diminta untuk
menggantikan posisi ayahnya, akan tetapi Syarif Hidayatullah memilih untuk
pulang ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam bersama Pangeran Cakrabuana.
Dalam perjalanannya ke Pulau Jawa, Syarif Hidayatullah singgah di beberapa
daerah, di antaranya Gujarat (selama tiga bulan), singgah di pondok saudaranya
yang berada di daerah Pasai (selama dua tahun), dan daerah Banten yang diketahui
sudah banyak masyarakatnya memeluk Islam.36
Setiba di Cirebon, ia membuka pondok berkat bantuan uwanya yaitu Haji
Abdullah Iman yang merupakan Kuwu Caruban dan mendapat tugas untuk
berdakwah di Gunung Sembung, dan menjadi guru agama Islam. Dengan datangnya
Syarif Hidayatullah ke Cirebon, Pangeran Cakrabuana alias Haji Abdullah Iman
kemudian menikahkan anaknya yang bernama Nyai Pakungwati dengan Syarfi
Hidayatullah sekaligus mengangkat Syarif Hidayatullah sebagai penggantinya untuk
memimpin Caruban dan bergelar Susuhunan Jati, Sunan Jati, atau Sinuhun
Caruban/Cerbon.37
Upacara penobatan Syekh Syarif Hidayatullah dilakukan pada tanggal 12
bagian terang bulan carita 1404 Saka (Maret/April 1479 M). Penobatan itu
didukung penuh oleh kalangan Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Ampel dan
melantik Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin Cirebon yang baru. Penobatan itu
juga ditandai dengan pemberian gelar kepada Syarif Hidayatullah sebagai “Ingkang
Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purbawisesa Penataagama Aulia Allah Ta‟ala
Kutubil Jaman, Kholifatu rasulillahi Sholulolhu Alaihi Wassalam”. Berdasarkan
gelar itu Syekh Syarif Hidayatullah lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati
yang mempunyai otoritas sebagai pemimpin agama di Tatar Sunda.38
Dengan
penobatan ini Syarif Hidayatullah tidak hanya sebagai seorang pemimpin secara
politis, tetapi juga pemimpin agama Islam di wilayah Sunda sebagai pengganti
Syekh Nurjati yang sudah wafat.
Langkah awal yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dihentikannya
pengiriman upeti garam dan terasi pada tahun 1482 yang seharusnya tiap tahun
dikirimkan ke Ibu kota Pakuan Pajajaran sebagai salah satu persembahan kerajaan
vasal kepada kerajaan induk. Sejak saat itu Cirebon bukan lagi sebagai negara vasal
dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Sementara untuk mempertahankan dan
mengantisipasi dari serangan Kerajaan Pakuan Pajajaran karena tidak mengirimkan
upeti seperti tahun-tahun sebelumnya, maka dibentuklah pasukan keamanan yang
disebut Pasukan Jagabaya. Pasukan ini dipimpin oleh seorang komandan yang
disebut Tumenggung, sedangkan untuk jumlah serta kualitasnya sangat memadai
36
Atja, Carita Purwaka Caruban…, h. 36.; Sulendraningrat, Babad Tanah Sunda…, h.
28-30. 37
Hardjasaputra, Cirebon dalam Lima…, h. 55.; Atja, Carita Purwaka Caruban…, h.
37. 38
P. S. Sulendraningrat (ed.), Sejarah Cirebon dan Silsilah Sunan Gunung Jati
Maulana Syarif Hidayatullah, (Cirebon: Sekretariat Sementara Keprabonan, 1984), h. 35.
78
dan ditempatkan di pusat kerajaan, pelabuhan serta tempat-tempat yang dikuasai
oleh Kesultanan Cirebon.39
Dalam rangka memperbaiki sistem pemerintahan, Sunan Gunung Jati berusaha
menata pemerintahan dari tingkat pusat sampai di tingkatan paling bawah selaras
dan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan kebutuhan masyarakat. Selain system
pemerintahan, ia juga menata gelar dan jabatan para pejabat pemerintahan. Untuk
kepala persekutuan masyarakat terkecil yang jumlah penduduknya 20 orang
dipimpin oleh Ki Buyut, beberapa unit kebuyutan disebut dengan nama dukuh/desa
yang dipimpin oleh seorang kuwu, kumpulan beberapa dukuh/desa dipimpin oleh
sorang Ki Gede serta kumpulan beberapa Gede dipimpin oleh seorang
Adipati/Tumenggung atau sekarang lebih dikenal dengan Bupati. Setiap pejabat
pemerintahan seperti Adipati, Tumenggung dan Bupati diwajibkan untuk hadir di
ibu kota negara dalam agenda menghadiri rapat bulanan yang disebut dengan istilah
Seba Keliwonan. Rapat ini biasanya dipimpin langsung oleh Sunan Gunung Jati di
Mesjid Agung Sang Cipta Rasa.40
Kesultanan Cirebon sebagai kekuatan politik di bagian barat pulau Jawa
mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, putera Nyi Mas
Rara Santang, adik Pangeran Cakrabuanakeduanya merupakan anak Prabu
Siliwangi dari Nyi Mas Subang Larang. Sunan Gunung Jati berhasil menggantikan
kedudukan pamannya sebagai penguasa Cirebon dengan memperluas wilayah
Cirebon mencakup seluruh wilayah pesisir utara, pedalaman, wilayah selatan hingga
ujung barat pulau Jawa yaitu wilayah Banten. Melalui beberapa penaklukan,
wilayah-wilayah yang dulunya dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran berhasil dikuasai
oleh Sunan Gunung Jati. Lama kelamaan, pengaruh Pajajaran semakin berkurang
dan akhirnya benar-benar jatuh pada tahun 1579. Singkatnya, di bawah
kepemimpinan Sunan Gunung Jati dan melemahnya pengaruh Kerajaan Pajajaran,
pada abad 16 Cirebon telah berhasil tampil sebagai penguasa tunggal di wilayah
bagian barat pulau Jawa.41
Kesultanan Cirebon dalam kepemimpinan Sunan Gunung Jati telah
berlangsung selama 66 tahun. Dalam Purwaka Tjaruban Nagari yang disalin
Sulendraningrat dan Babad Tjerbon yang ditulis Ki Murtasiah edisi Brandes
menyebutkan bahwa istri Sunan Gunung Jati yang pertama adalah Nyi Mas
Babadan. Penjelasannya adalah di tahun 1471 Syarif Hidayatullah menikah dengan
Nyi Babadan di Babadan Cirebon. Pada tahun 1477 Nyi Babadan wafat tanpa putra.
Dua tahun sebelum wafatnya Nyi Babadan, Syarif Hidayatullah bedakwah ke
Banten dan menikah dengan Nyi Kawunganten di tahun 1475. Kemudian di tahun
39
Atja, Carita Purwaka Caruban…, h. 37.; Hardjasaputra, Cirebon dalam Lima…, h.
56. 40
Pada tahun 1530 wilayah Kesulatanan Cirebon sudah meliputi separuh Propinsi Jawa
Barat yang sekarang. Namun, sebagian penduduk masih beragama non Islam. Ini menjadi
sebuah tantangan kepada setiap pemimpin daerah untuk menyebarkan agama Islam di
wilayahnya masing-masing. Lihat U. Sunardjo, Masa Kejayaan Kerajaan Cirebon: Kajian
dari Aspek Politik dan Pemerintahan, (Cirebon: Yayasan Keraton Kasepuhan, t.th.), h. 38. 41
D. N. Rosyidin, dan A. Syafaah, A. Keragaman Budaya Cirebon: Survey atas Empat
Entitas Budaya Cirebon, (Cirebon: Elsi Pro, 2016), h. 26-27.
79
1478 Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyi Pakungwati. Tiga tahun selisih
pernikahannya dengan Nyi Pakungwati, Syarif Hidayatullah menikahi Ong Tien
(putri Tionghoa) di tahun 1481. Pada tahun 1486 menikah dengan Syarifah
Baghdad. Pada tahun 1485 putri Tionghoa wafat, Syarif Hidayatullah menikah lagi
dengan Nyi Tepasari. Sekalipun Syarif Hidayatullah melakukan pernikahan yang
berulang-ulang, namun tidak pernah memiliki istri lebih dari empat. Keempat
isterinya itu masing-masing menetap di Kawunganten Banten, Pakungwati Cirebon,
Syarifah Baghdad di Pesambangan dan Nyi Tepasari dari Majapahit.42
Pada masa pemerintahannya, sebelum lengser, Sunan Gunung Jati menetapkan
pengganti kepemimpinan Cirebon. Berdasarkan pertimbangan kemampuan dan
kapasitas yang mumpuni, maka pada tahun 1511, ditetapkan Pangeran Bratakelana
yang masih berusia 23 tahun. Dalam menetapkan penggantinya Sunan Gunung Jati
tidak berdasarkan asas senioritas ataupun yang diambil dari permaisuri.43
Namun,
setelah setahun dari pengangkatannya, dan sekembalinya dari Demak pasca
menikah dengan Nyi Mas Ratu Nyawa, Pangeran Bratakelana gugur dihadang dan
diserang oleh bajak laut di perairan Gebang pada tahun 1512. Sunan Gunung Jati
nampaknya lebih tertarik pada kegiatan penyebaran Islam daripada urusan
pemerintahan, sehingga mulai tahun 1528 pemerintahan diserahkan kepada
Pangeran Pasarean -puteranya dengan Nyai Tepasari dari Majapahitsetelah
gugurnya Pangeran Bratakelana.44
Pada masa pemerintahan Pangeran Pasarean, ia
mendapat pengawasan langsung dari Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1529,
Pangeran Pasarean melengkapi bangunan keraton seperti Bale Kambang Dalem
Arum Kedalem, Bangsal Agung, Bangunan Kaputren, Bangsal Pringadani, Jinem
Pangrawit, Taman Bunderan dan Dewandaru. Dapat dikatakan bahwa masa
Pangeran Pasarean memerintah cukup singkat yaitu sekitar 18 tahun.45
Sunan Gunung Jati akhirnya menikahkan Pangeran Pasarean dengan janda
kakaknya, yaitu Nyi Mas Ratu Nyawa. Sementara kakak Pangeran Pasarean yang
bernama Ratu Ayu dinikahkan dengan Fatahillah. Akan tetapi, Pangeran Pasarean
dibunuh oleh Arya Panangsang pada 1546, sehingga untuk mengisi kekosongan
tersebut, Kesultanan Cirebon dipimpin oleh Sunan Cirebon dan Dipati Swarga.
Pada akhirnya Pangeran Swarga menikah dengan Putri Fatahillah yaitu Nyi Mas
Wanawati Raras yang dikemudian hari akan menurunkan Panembahan Cirebon.
Pada tahun 1552, Dipati Swarga menderita sakit sehingga tidak dapat menjalankan
42
Sunanto, “Syarif Hidayatullah Seorang…,” h. 73-75. 43
Pernikahan pertama Sunan Gunung Jati dengan Nyi Mas Babadan tidak dikarunai
keturunan dan di usia pernikahannya yang keempat tahun, Nyi Mas Babadan meninggal.
Begitu juga pernikahannya dengan Putri Ong Tin Nio dan Nyi Mas Pakungwati juga tidak
dikarunai keturunan. Sunan Gunung Jati baru dikaruniai keturunan ketika menikah dengan
Nyi Mas Kawunganten pada 1475, yakni Ratu Winaon dan Pangeran Sebakingkin (Pangeran
Hasanudin). Kemudian, pernikahannya dengan Syarifah Baghdad pada 1485, Sunan Gunung
Jati dikarunai dua orang putra bernama Pangeran Jayakelana dan Pangeran Bratakelana. 44
Hardjasaputra dan Haris, Cirebon dalam Lima…, h. 68. 45
U. Sunardjo, Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cerbon,
1479-1809, (Bandung: Tarsito, 1983), h. 67.
80
roda pemerintahan Kesultanan Cirebon, sehingga Fatahillah46
yang juga merupakan
mertuanya menggantikan posisinya dalam menjalankan kekuasaan.47
Pada tahun 1568, Kesultanan Cirebon berduka karena Sunan Gunung Jati yang
merupakan salah satu raja dan Wali Songo meninggal dunia. Ia dimakamkan di
Astana Gunung Sembung atau lebih dikenal dengan nama Astana Gunung Jati. Hal
ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Purwaka Caruban Nagari bahwa Sunan
Gunung Jati lahir pada tahun 1448 M dan meninggal pada tahun 1568 M dengan
usia 120 tahun. Sepeninggal wafat Sunan Gunung Jati, Kesultanan Cirebon
kehilangan salah satu sosok raja yang bijaksana sekaligus juga tokoh penyebar
agama Islam.48
Pasca kepemimpinan Sunan Gunung Jati, tidak ada keturunan
langsung yang dapat menggantikannya sebagai raja Cirebon. Karena ketiga anak
Sunan Gunung Jati yaitu Pangeran Pasarean, Pangeran Jayakelana, dan Pangeran
Bratakelana telah terlebih dahulu meninggal. Putra yang masih hidup adalah
Pangeran Sebakinkin (Pangeran Hasanudin), namun ia sudah menjadi salah satu
penguasa Banten. Maka, berdasarkan kesepakatan sesepuh Cirebon, ditunjuklah
Fatahillah untuk memimpin Kesultanan Cirebon, tetapi masa kepemimpinannya
terbilang cukup singkat, yakni sekitar tahun 1568 M-1570 M.49
Berdasarkan
penelusuran penulis, sedikit informasi yang menyebutkan sepak terjang dan
kepemimpinan Fatahillah saat memimpin Kesultanan Cirebon.
Pasca Fatahillah wafat, tambuk kepemimpinan diserahkan kepada Pangeran
Emas yaitu putra tertua Pangeran Dipati Carbon. Ia mendapatkan gelar sebagai
Panembahan Ratu atau Panembahan Ratu I. Pada awal pemerintahannya, Cirebon
sudah mencapai kemajuan yang signifikan dan berkembang pesat, hal itu dapat
dilihat dengan ramainya pelabuhan Cirebon karena terbukanya aktivitas
perdagangan, dan struktur pemerintahan ketika itu sudah tersusun rapih karena
kepala-kepala wilayah atau yang bergelar Ki Gedeng sudah banyak dan tunduk
kepada Raja Cirebon. Di samping itu, perekonomian daerah ini juga sudah semakin
maju dibanding dengan masa-masa sebelumnya. Ketersediaan tranportasi sungai
yang menghubungkan antara sungai-sungai kecil dengan pelabuhan Cirebon,
sampai ke daerah pedalaman turut mempercepat perkembangan ekonomi di daerah
setempat. Produksi di sekitar pelabuhan seperti ikan asin, garam dan terasi sangat
diminati oleh masyarakat pedalaman, dan masyarakat pedalaman menyiapkan
ketersediaan beras, hasil bumi dan kayu-kayuan yang cukup melimpah. Sehingga
46
Fatahillah ditunjuk sebagai salah satu pemegang tertinggi kekuasaan di Kesultanan
Cirebon. Ia merupakan salah satu panglima perang Cirebon, tangan kanan serta penasehat
terpercaya Sunan Gung Jati. Selain itu, sebelum menjadi menantu, Fatahillah telah ikut
berjasa dalam mengalahkan aramada Portugis dan berhasil merebut Sunda Kelapa menjadi
wilayah kekuasaan Islam. 47
Hardjasaputra, Cirebon dalam Lima…, h. 68-69.; Atja, Carita Purwaka Caruban…,
h.41. 48
Atja, Carita Purwaka Caruban…, h. 68. 49
Dapat terlihat dari pengangkatan Fatahillah sebagai salah satu pemimpin Cirebon,
walaupun berstatus sebagai menantu, Sunan Gunung Jati melihat calon pemimpin
berdasarkan kapasitas dan cakapnya memimpin. Lihat Z. Masduqi, Cirebon dari Kota
Tradisional Ke Kota Kolonial, (Cirebon: Nurjati Press, 2011), h. 45.
81
dengan dibangunnya sarana dan prasana itu membuat perekonomian mengalami
peningkatan yang cukup signifikan.50
Selain yang disebutkan di atas, pembangunan di wilayah keraton juga
diperbanyak oleh Panembahan Ratu I. Pada tahun 1596, Panembahan Ratu I
membangun pagar tembok yang mengelilingi kota dengan tinggi dua meter dan
mempunyai beberapa pintu gerbang. Pagar tembok ini merupakan salah satu
persembahan Panembahan Senopati dari Mataram kepada Panembahan Ratu I yang
sudah dianggap sebagai gurunya. Pembangunan tembok tersebut bertujuan untuk
memperkuat pertahahan Cirebon, mengingat daerah ini merupakan basis pertahanan
Mataram di bagian Barat. Selain itu, fungsi pembangunan tembok merupakan taktik
Mataram untuk menanamkan pengaruhnya di Kerajaan Cirebon, hal ini dikarenakan
penguasa Banten ingin menguasai Cirebon.51
Panembahan Ratu lebih memfokuskan perhatiannya pada penguatan kehidupan
keagamaan seperti yang dijalankan oleh Syarif Hidayatullah. Ia lebih banyak
memerankan diri sebagai seorang ulama dari pada seorang umaro. Kedudukannya
sebagai seorang ulama membuatnya lebih banyak perhatian kepada masalah
keagamaan daripada masalah politik dan ekonomi dalam menjalankan
pemerintahannya. Kedudukannya ini pula yang menyebabkan Sultan Mataram
segan memasukkan Cirebon sebagai daerah bawahannya. Dalam rangka
mempererat hubungan dengan Mataram akhirnya dilakukan perkawinan politis
antara Panembahan Ratu dan Nyai Mas Ratu Lampok Angrorosputeri Sultan
Pajang pada tahun 1571 M. Perkawinan politis juga dilakukan oleh cucu kedua
belah pihak, yaitu Panembahan Girilaya dengan puteri Sunan Amangkurat 1.52
Pada tahun 1649, Panembahan Ratu I meninggal dunia. Kursi kepemimpinan
selanjutnya dipercayakan kepada cucunya yakni Pangeran Girilaya (Pangeran
Karim/Pangeran Rasmi). Pangeran Girilaya kemudian mendapatkan gelar sebagai
Panembahan Ratu II. Pada masa pemerintahannya, Cirebon mendapatkan tekanan
dari Mataram di bawah kepemimpinan Sunan Amangkurat I. Hal ini disebabkan
karena Panembahan Ratu II merupakan menantu dari Sunan Amangkurat I
Mataram, sehingga ketika ia dilantik membuat Amangkurat I berambisi untuk
menguasai Cirebon.53
Ketika Panembahan Girilaya yang tidak lain adalah merupakan menantu Sultan
Amangkurat I dari Kerajaan Mataram menjadi penguasa Cirebon, keadaan
mengalami perubahan. Cirebon menjadi rebutan pengaruh dua kekuatan politik
Islam yaitu Mataram dan Banten. Karena Cirebon merupakan pelabuhan penting,
maka Cirebon dijadikan buffer power-nya Mataram. Sebagai pelabuhan penting,
Cirebon dianggap memiliki kemampuan untuk mengembangkan perdagangan baik
lokal maupun internasional. Secara ekonomi, Cirebon memiliki kemandirian karena
tidak hanya menggantungkan ekonominya pada produk-produk agraris tetapi juga
50
Rosyidin, Kerajaan Cirebon, h. 120. 51
Hardjasaputra, Cirebon dalam Lima…, h. 70. 52
Yani, A. “Pengaruh Islam Terhadap Makna Simbolik Budaya Keraton-Keraton
Cirebon. Holistik, vol. 12, no. 1, 2011, h. 181-196. 53
H. Erwantoro, “Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon”. Patanjala, vol. 4, no. 1, 2012, h.
166-179.
82
pada perdagangan yang bersumber dari eksternal.54
Kekuatan Cirebon tersebutlah
yang menurut penulis digunakan Mataram untuk melihat Cirebon sebagai wilayah
strategis dalam kerangka operasi militer Mataram ke Batavia yang sudah sejak awal
abad ke-17 dikuasai VOC.
Masa pemerintahan Panembahan Ratu II merupakan masa yang yang cukup
berat dan sulit bagi Cirebon, sebab Sunan Amangkurat I menganggap bahwa
kedaulatan, kewibawaan dan kemerdekaan Cirebon sebagai sebuah Kerajaan Islam
sudah berakhir, bahkan Sunan Amangkurat I berhasil mengambil Ciamis sebagai
wilayahnya, sehingga wilayah Cirebon tinggal meliputi Cirebon, Majalengka,
Indramayu dan Kuningan. Campur tangan Mataram didasari dengan keinginan
menjadi negara super power di Nusantara serta dapat mengusir VOC dari Pulau
Jawa. Salah satu starteginya adalah dengan menguasai Cirebon, karena Cirebon
memiliki pelabuhan yang strategis untuk jalur perdagangan internasional. Selain itu,
Cirebon dianggap bisa dijadikan benteng untuk menahan laju VOC yang berpusat di
Batavia, sehingga membuat Mataram bisa melakukan ekspansi ke daerah timur.55
Pada masa Amangkurat I, Mataram lebih mudah memasukan pengaruhnya bagi
Cirebon, karena Panembahan Ratu II adalah menantunya sendiri. Ia mengawasi
sendiri aktivitas pemerintahan Cirebon, sehingga satu waktu ia beranggapan bahwa
Cirebon sedang merintis kekuatan dengan Kesultanan Banten untuk melakukan
pemberontakan terhadap Mataram. Pada tahap ini Amangkurat I bersekutu dengan
VOC dan berambisi untuk menguasai Cirebon. Hal ini karena, ia mendapat
pengaruh dan bujukan dari VOC untuk menguasai Cirebon termasuk pelabuhan
Cirebon.56
Pada tahun 1650, Amangkurat I mengundang Panembahan Ratu II untuk
berkunjung ke Mataram dengan alasan untuk memberikan penghormatan sebagai
Raja Cirebon. Undangan tersebut diamini oleh Panembahan Ratu II dengan
berangkat ke Mataram bersama kedua anaknya yakni Pangeran Martawijaya dan
Pangeran Kartawijaya, namun sesampainya di Mataram, mereka dijadikan tahanan
oleh Amangkurat I, dan dilarang untuk kembali ke Cirebon. Hal ini merupakan
taktik Amangkurat I untuk melemahkan Kesultanan Cirebon. Masih dalam posisi
sebagai tahanan pada tahun 1662, Panembahan Ratu II meninggal di Mataram dan
dimakamkan di Imogiri Yogyakarta. Hal ini terjadi ketika ia menjadi tahanan rumah
bersama kedua putranya. Pasca meninggalnya Panembahan Ratu II, Cirebon terjadi
kekosongan kepemimpinan, namun tidak membuat dan menyebabkan kelumpuhan
dan kehancuran.57
54
H. M. Ambary, “Peranan Cirebon sebagai pusat perkembangan dan penyebaran
Islam”, dalam S. Zuhdi, Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra, (Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan kebudayaan RI, 1996), h. 47-48. 55
F. T. Deviani, “Perjanjian 7 Januari 1681 dan Implikasinya Terhadap Kehidupan
Sosial Politik Ekonomi di Kerajaan Cirebon (1681 M-1755 M)”. Tamaddun, vol. 4, no. 1,
2016, h. 123-146.; H. Djajadiningrat, Beberapa Catatan Mengenai Kerajaan Jawa Cerbon
pada Abad-abad Pertama Berdirinya, (Jakarta: Bhratara, 1973), h. 69-71.; Hardjasaputra,
Cirebon dalam Lima…, h. 87-88. 56
Rosyidin, Kerajaan Cirebon, h. 140. 57
Lasmiyati, “Keraton Kanoman di Cirebon (Sejarah dan Perkembangannya)”.
Patanjala, vol. 5, no. 1, 2013, h. 131-146.; Atja, Carita Purwaka Caruban…, h. 73.; H. R.
83
Pada saat terjadi kekosongan kepemimpinnan, Kesultanan Banten mulai
melakukan campur tangan. Hal ini dilakukan ketika Panembahan Ratu II dan kedua
anaknya menjadi tahanan oleh Mataram. Dengan wafatnya Panembahan Ratu II,
melalui perdebatan yang sengit dan mendalam, para pejabat Cirebon akhirnya
meminta bantuan dan perlindungan dari Kesultanan Banten. Permintaan itu
direspon positif oleh Sultan Ageng Tirtayasa selaku penguasa Banten, dan
diputuskan bahwa pengganti Kesultanan Cirebon adalah Pangeran Wangsakerta,
yang tidak lain adalah merupakan putra Panembahan Ratu II dari selir sebagai Raja
Cirebon. Pengangkatan Pangeran Wangsakerta sebagai Raja Cirebon terjadi karena
dengan pertimbangan bahwa kedua anak Panembahan Ratu II yakni Pangeran
Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya masih menjadi tahanan Mataram. Dengan
ditetapkannya Pangeran Wangsakerta sebagai penguasa Cirebon menandakan
bahwa Sultan Ageng Tirtayasa mempunyai kekuatan besar untuk melindungi
Cirebon dari kendali politik Mataram yang dimainkan Amangkurat I.58
Pasca meninggalnya Panembahan Ratu II (Panembahan Girilaya), pada tahun
1677 terjadi perpecahan di dalam Kesultanan Cirebon. Pecahnya Kesultanan
Cirebon tidak terlepas dari campur tangan dan pengaruh Kesultanan Banten dan
Kesultanan Mataram. Kedua kekuatan tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni
sama-sama ingin menguasai Cirebon. Setelah dua putera Panembahan Ratu II, yaitu
Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kertawijaya berhasil dibebaskan oleh
Trunojoyo dari cengkeraman kakeknya (Sunan Amangkurat I), keduanya kemudian
dibawa ke Kediri untuk selanjutnya dibawa ke Sultan Ageng Tirtayasa di Banten.
Keduanya disambut dengan upacara penghormatan, dan yang hadir pada saat itu
adalah adiknya yakni Pangeran Wangsakertayang mengambil alih kepemimpinan
selama kedua kakaknya menjadi tawanan Mataram. Pada saat itu, Sultan Ageng
Tirtayasa membagi tiga kekuasaan atas Kesultanan Cirebon. Ketiga Pangeran
Cirebon mendapat gelar sultan dari Sultan Banten dan dilantik menjadi penguasa
Cirebon. Gelar Sultan Muhammad Syamsuddin diberikan kepada Pangeran
Martawijaya sekaligus menjadi Sultan Kasepuhan, gelar Sultan Muhammad
Badrudin diberikan kepada Pangeran Kartawijaya sekaligus menjadi Sultan
Kanoman, dan Pangeran Wangsakerta dilantik menjadi Panembahan Cirebon,59
namun ia tidak membangun kesultanan seperti kedua saudaranya. Dengan pecahnya
menjadi dua kasultanan, ini kemudian menimbulkan sebuah masalah baru dan titik
balik dalam hal campur tangan dari pihak lain seperti VOC. Dalam tahap ini,
membuat eksistensi Cirebon semakin menurun.60
Keterlibatan VOC dalam pemerintahan Kesultanan Cirebon terjadi ketika
Sultan Sepuh I meminta bantuan VOC untuk membereskan perpecahan yang terjadi
dalam kekuasaan Cirebon. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya, perpecahan itu
justru dimanfaatkan oleh VOC untuk merebut dan menjadikan Cirebon sebagai
B. Irianto dan K. T. Sutarahardja, Sejarah Cirebon: Naskah Keraton Kacirebonan,
(Yogyakarta: Deepublish, 2013), h. 92-93. 58
Erwantoro, “Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon”, h. 170-183. 59
Hardjasaputra dan Haris, Cirebon dalam Lima…, h. 99.; Atja , Purwaka Caruban
Nagari…, h. 73-74. 60
Atja, Purwaka Caruban Nagari…, h. 46.
84
negara bawahan (vassal state). Konflik yang berkepanjangan membuat VOC mudah
untuk melakukan adu domba masing-masing sultan. Pada tahun 1681, VOC
mengadakan perjanjian persahabatan di antara para sultan untuk mengatasi konflik,
dan VOC bertindak sebagai penegahnya. Perjanjian itu berlangsung di Keraton
kasepuhan pada tanggal 7 Januari 1681, dan yang melakukan perjaanjian adalah
Sultan Sepuh I, Sultan Anom I, Panembahan Cirebon, Raksanegara, Anggaderaksa,
Purbanegara, Anggadeprana, Anggaraksa, Nayapati, Jacob van Dyck dan Jochem
Michielse.61
Ada beberapa hasil kesepakatan yang merugikan dalam perjanjian itu, yakni
Cirebon diperintah oleh Sultan Sepuh I, Sultan Anom I, dan Panembahan Cirebon.
Akan tetapi, mengenai batas kekuasaan belum ditentukan. Secara politik ada
beberapa poin dalam perjanjian ini yaitu Cirebon merupakan salah satu daerah
protektorat VOC sehingga membuat sultan tidak lagi mendapat atau berhak penuh
untuk memimpin Cirebon, atau dengan kata lain, adanya pembatasan akan wewenag
sultan untuk memimpin Cirebon. Selain itu, antara kedua belah pihak yakni Cirebon
dan VOC harus selalu menjalin persahabatan dan saling percaya dan Sultan Cirebon
tidak boleh membuat basis pertahanan di daerah perbatasan dan wilayah panjang
tanpa ada izin dari VOC. Kemudian, VOC boleh membangun benteng di Cirebon.62
Padahal, pertahanan dari kesultanan yang kuat diperlukan untuk mempertahankan
wilayah kekuasaannya.
Kehadiran VOC di Cirebon terutama setelah adanya perjanjian pada 7 Januari
1681 telah membawa perubahan pada segala sendi kehidupan masyarakat Cirebon,
ditambah lagi bahwa VOC berusaha mengambil peran, dan melakukan intervensi
pada politik Kesultanan Cirebon. Keterlibatan VOC dalam urusan pemerintahan
telah mengakibatkan terjadinya pergeseran peran seorang sultan. Sultan tidak lagi
punya otoritas kekuasaan politik karena peran itu sudah diambil alih oleh VOC. Hal
itu juga dapat dilihat ketika VOC mengeluarkan peraturan pergantian sultan pada
tahun 1752. Sultan hanya mengurusi urusan keagamaan dan kebudayaan. Eksistensi
sultan menjadi lemah dan tidak lagi memiliki kekuatan karena otoritas politik
berada ditangan VOC.63
Perjanjian 18 Januari 1752 sebagaimana yang disebutkan di atas, VOC
mengeluarkan peraturan mengenai pergantian sultan dan sultan-sultan Cirebon
kehilangan kekuasaan politiknya. Ada dua garis besar dalam peraturan tersebut
yaitu pergantian tahta harus didasarkan pada warisan ayah kepada anak, dan jika
sultan meninggal dan tidak mempunyai keturunan langsung maka kekayaan beserta
peranan dalam sebuah pemerintahan harus dibagikan kepada para sultan yang lain.
Contohnya, ketika Panembahan Cirebon meninggal dunia, ia tidak meninggalkan
keturunan maka kekayaan dan daerah kekuasaanya oleh VOC dibagikan kepada
61
Deviani, “Perjanjian 7 Januari 1681 dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial
Politik Ekonomi di Kerajaan Cirebon (1681 M-1755 M)”, h. 123-146. 62
Masduqi, Cirebon dari Kota…, h. 70. 63
Tendi, “Surat Perjanjian 7 Januari 1681: Edisi Diplomatik Naskah.”. Jurnal
Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, vol. 8, no. 1, 2020, h. 39-58.; Deviani,
“Perjanjian 7 Januari 1681 dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Politik Ekonomi di
Kerajaan Cirebon (1681 M-1755 M)”, h. 123-146.
85
Kasepuhan dan Kanoman. Di samping itu, VOC mengatur tentang gelar sultan,
dimana gelar sultan ini hanya diberikan kepada dua penguasa saja, dan pemimpin
kesultanan selanjutnya hanya boleh bergelar pangeran. Setiap terjadi pergantian
kepemimpinan di kasultanan, VOC mempunyai peran yang besar, seperti ketika
Sultan Anom IV wafat yang seharusnya menjadi penggantinya adalah puteranya
yaitu Pangeran Surianegara, namun VOC mengangkat adik seayahnya yaitu
Pangeran Surantaka. Dengan begitu kuatnya peran VOC, sampai bisa mengusir
beberapa pangeran yaitu Pangeran Surianegara, Pangeran Lautan untuk keluar dari
keraton.64
Pengaruh VOC di Cirebon semakin berkuasa setelah membangun loji atau
benteng di kawasan Pelabuhan Cirebon. VOC mempunyai hak untuk membangun
benteng pertahanan di Cirebon, namun sebaliknya, pihak kesultanan tidak diizinkan
membentuk sebuah pertahanan di sekitar keraton. Pembangunan benteng pertama
dilakukan setelah penghancuran tembok keliling Cirebon, yang juga merupakan
persembahan dari Pangeran Senopati. Dari material inilah benteng pertama di
Cirebon dibangun di sekitar Pelabuhan Cirebon. Benteng tersebut diberi nama De
Fortrese de Bescherming (Benteng Perlindungan). Lokasi benteng di sekitar
pelabuhan menandakan bahwa VOC ingin menguasai dan mengontrol aktivitas
perdagangan Cirebon karena pelabuhan ini merupakan salah satu pusat
perekonomian internasional.65
Dengan pengaruh kuatnya sebagaimana penulis sebutkan di awal, VOC
merampas kekuasaan politik sultan. Semua keputusan sultan yang ditandatangani
harus atas perintah dan persetujuan VOC. Sultan dalam kondisi ini kehilangan
kekuasaan politiknya. Karir dan gelarnya hanya sebatas simbol, karena sebenarnya
yang menjalankan pemerintahan adalah VOC. Contohnya dalam perjanjian 8
September 1688 pasal 22 yang menyatakan bahwa gelar sultan dan panembahan
hanya digunakan dalam surat dan naskah dari kompeni, sedangkan di luar itu
disebut dengan raja atau bahkan Pangeran Cirebon dan nama asli seperti
Martawijaya, Kartawijaya dan Wangsakerta.66
Dalam penelusuran penulis, setidaknya ada beberapa perjanjian yang dilakukan
untuk menengahi konflik antar Sultan yaitu perjanjian persahabatan antara sultan
dengan dimediasi VOC, pada tanggal 7 Januari 1681, dilanjutkan perjanjian pada 4
Desember 1685, perjanjian 5 Desember 1688, Perjanjian 4 Agustus 1699, perjanjian
17 Januari 1708, dan perjanjian 18 Januari 1752. Semua perjanjian yang digelar
pada sebenarnya tidak menguntungkan Cirebon, malah membuatnya rugi, akan
tetapi para sultan tidak mengajukan keberatan atau gugatan terhadap hasil-hasil
perjanjian karena mereka sudah terikat dengan kontrak perjanjian.67
64
M. S. Bochari & Wiwi Kuswiyah, Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon, (Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional, 2001), h. 45. 65
Hardjasaputra, Cirebon dalam Lima…, h. 68. 66
Tim Peneliti, Sejarah Cirebon Abad Ketujuh Belas, (Bandung: Pemda TK. I, 1991),
h. 252. 67
Perjanjian 7 Janauri 1681 berdampak besar bagi Kesultanan Cirebon, terutama di
sosial, ekonomi dan politik. Implikasinya adalah dengan melemahnya kekuasaan politik di
Kesultanan Cirebon dengan banyaknya campur tangan VOC dalam pemerintahan kesultanan
86
Isi perjanjian tanggal 7 Januari 1681 antara Cirebon dan VOC sangat
memengaruhi perjalanan Cirebon sebagai kota dagang. VOC mendapatkan hak
monopoli impor dan ekspor dengan bebas bea impor yang sebelumnya pernah
dikenakan keraton sebesar dua persen dari nilai barang. Perjanjian itu juga
merugikan penduduk lokal yang harus mendapat lisensi dari VOC yang ingin
melakukan pelayaran. Kapal-kapal tidak boleh sembarangan masuk pelabuhan
kecuali atas ijin VOC. Tanaman lada yang ditanam di Cirebon diatur oleh VOC dan
VOC pula yang menentukan harganya.68
Dengan perjanjian tersebut, secara politis
Cirebon berada di bawah kendali langsung VOC.
Dalam rangka menyebarkan paham adu domba, VOC mengutus Francois Tack
untuk melakukan pendekatan dengan para sultan, hal ini bertujuan supaya para
sultan berselisih paham. Hubungan yang dekat antara Francois Tack dan Sultan
Anom I, membuat Sultan Sepuh I dan Panembahan Cirebon iri dan merasa curiga,
ditambah lagi batas-batas kekuasaan Cirebon belum ditentukan, bahkan dengan
semakin intensnya kedua orang itu mengakibatkan konflik dan membuat sebuah
perjanjian. Dalam perjanjian yang digelar pada 8 September 1688, terdapat 26 pasal
dan naskah perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pihak Cirebon
diwakili oleh Sultan Sepuh I beserta putra pertamanya Sultan Dipati Anom, Sultan
Anom I beserta putra tertuanya Pangeran Ratu, dan Panembahan Cirebon beserta 12
orang mantri, sedangkan pihak VOC dipimpin oleh Johanes de Hartog.69
Setelah VOC bubar pada 1799, kekuasaan politik Cirebon diambil alih oleh
Pemerintah Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Cirebon
masuk dalam wilayah keresidenan sekaligus sebagai ibu kota distrik dengan
Gubernur Jenderalnya H. W. Daendels. Status sultan diberhentikan dan dijadikan
sebagai bupati yang diberi gaji, sehingga sultan mendapat pensiunan.70
Gubernur
Jenderal Daendels kemudian menerapkan sistem pemerintahan sentralistik yakni
memerintah rakyat secara langsung tanpa adanya perantara sultan atau bupati. Ia
menurunkan kedudukan sultan dan bupati, dan menjadikan mereka sebagai pegawai
tinggi pemerintah kolonial serta mendapatkan gaji. Oleh karena itu Daendels,
membuat kedudukan seorang sultan dan bupati tidak berlaku lagi termasuk di
Cirebon. Pada tanggal 2 Februari 1809, Daendels mengeluarkan peraturan
Reglement op het Beheer van Cheribonsche Landen71
(Peraturan tentang
dengan cara mempersempit kekuasaan sultan. Lihat “Naskah Perjanjian 7 Janauri 1681”,
dengan Sumber Arsip Cirebon No. 38.3 Arsip Nasional Republik Indonesia. Lihat juga
Deviani, “Perjanjian 7 Januari 1681 dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Politik
Ekonomi di Kerajaan Cirebon (1681 M-1755 M)”, h. 123-146. 68
S. T. Sulistiyono, Dari Lemah Wungkuk Hingga Cheribon: Pasang Surut
Perkembangan Kota Cirebon Sampai Awal Abad XX, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1997), h. 85. 69
Hardjasaputra, Cirebon dalam Lima…, h. 112. 70
Lisa Susanti, “Pengaruh Kolonial Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Cirebon
Tahun 1752-1830”. Jurnal Prodi Ilmu Sejarah, vol. 3, no. 3, 2018, h. 274-288.; Sulistiyono,
Dari Lemah Wungkuk…, h. 87. 71
Peraturan sebagaimana di atas terdiri atas: Ketentuan Umum (6 pasal); Bagian
Pertama, tentang Prefek (32 pasal); Bagian Kedua, Para Sultan, Bupati, dan Pemerintahan
Daerah Lebih Lanjut (31 pasal); Bagian Ketiga, soal Pajak, Kerja Pengabdian dan
87
Penguasaan atau Pemerintah Daerah Cirebon) yang menyatakan bahwa
pemerintahan Cirebon ditetapkan sebagai prefecture atau identik dengan sistem
karesidenan. Dengan adanya keputusan tersebut, membuat para sultan menjadi
pegawai pemerintahan kolonial Belanda serta kepala pemerintahan diganti oleh
seorang bupati yang diangkat langsung oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda.
Merujuk pada catatan John Crawfurd, Boulger mengatakan bahwa hingga masa
jabatan Daendels dan Janssens, penduduk Cirebon dikenakan delapan jenis
pungutan.72
Pertama, kontingen, sebesar lima belas persen dari total padi hasil
panen, tetapi pada kenyataannya diterapkan secara seenaknya. Kedua, pajak per
kepala (poll-tax) atau pajak atas keluarga, sebagian dipungut atas nama pemerintah,
sebagian lagi atas nama kepala setempat. Ketiga, pajak pasar atau tol. Pajak ini
dipungut untuk setiap barang atau komoditas yang dihasilkan dari pertanian,
manufaktur, dan hasil kerajinan tangan. Keempat, pajak pemotongan sapi. Pajak ini
berdampak pada harga makanan dan pembatasan terhadap upaya pembiakan hewan
serbaguna sebagaimana dimaksud. Kelima, pajak penginapan dan makanan bagi
pengembara, pengangkutan, bagasi, dan penyimpanan semua barang. Keenam,
kewajiban untuk membangun dan memperbaiki jembatan, jalan, dan bangunan
publik di sepanjang negeri (Cirebon). Ketujuh, kewajiban untuk menanam dan
menyetor dalam jumlah yang memadaiberbagai produk demi kepentingan ekspor,
terutama kopi. Kedelapan, pajak persepuluhan. Pada sebenarnya 1/20 dari total padi
hasil panen, dialokasikan untuk tujuan keagamaan dan pembayaran opsional, tetapi
jarang sekali ditangguhkan.
B. Perkembangan Daerah dan Masyarakat Cirebon
1. Daerah Cirebon
Wilayah Cirebon adalah wilayah pesisir utara paling timur di provinsi Jawa
Barat. Perbatasan timur dan tenggara adalah provinsi Jawa Tengah, perbatasan
selatan adalah Kabupaten Ciamis, perbatasan barat adalah Kabupaten Sumedang
dan Subang, sedangkan perbatasan utara adalah laut Jawa. Secara administrasi,
wilayah ini terdiri dari empat kabupaten (Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan
Majalengka), dan wilayah Cirebon dikategorikan sebagai wilayah padat penduduk
di Indonesia. Menurut Abdurrahman yang dinamakan daerah Cirebon dewasa ini
adalah wilayah bekas Keresidenan Cirebon, yang terdiri dari Kabupaten Cirebon,
Kuningan, Majalengka, Indramayu dan Kotamadya Cirebon. Sementara yang
dikenal sebagai Cirebon dalam sejarah kuno ialah daerah yang terletak di sebelah
utara ujung paling timur Pulau Jawa bagian barat.73
Kewajiban-kewajiban Lain Penduduk Pribumi (16 pasal); Bagian Keempat, terkait
Pengadilan Negeri (11 pasal); Bagian Kelima, Perihal Polisi, Pembuatan Jalan, dan Layanan
Pos (31 pasal). Lihat J. A. van der Chijs, Nederlansch-Indisch Plakaatboek 1602-1811.
Vijftiende Deel (1808-1809). (Batavia/'s Hage: Landsdrukkerij/M. Nijhoff, 1896), h. 474-
513. 72
Demetrius C. Boulger, The Life of Sir Stamford Raffles, (London: Horace Marshal &
Son, 1897), h. 115. 73
Abdurrahman, Cerbon, h. 11.
88
Cirebon daerahnya seluas 6790 km2, dan pada akhir tahun 1905 berpenduduk
1.700.000 jiwa. Daerah ini dihuni oleh orang kulit putih, berjumlah 1.200 orang,
Tionghoa 23.000 orang dan Arab 2.900 orang, serta orang-orang asing timur
lainnya. Di bagian selatan berbahasa sunda, di bagian utara campuran bahasa Jawa
dengan tiga macam logat, antara lain di daerah Indramayu, di bagian utara Cirebon
dengan logat Cirebon, sedangkan di ujung timur distrik Losari dengan logat Tegal.
Tentang asal mula penduduk Cirebon oleh Kern dikatakan berasal dari Jawa, sebab
Cirebon merupakan tempat pemberhentian pedagang-pedagang Jawa di daerah
Sunda.74
Menurut data BPS Kabupaten Cirebon jumlah penduduk Cirebon tahun
2019 berjumlah 322.322 jiwa.
Sebenarnya, Cirebon sudah dikenal sejak awal abad ke-15. Merujuk Purwaka
Tjaruban Nagari,75
nama Cirebon dahulunya adalah Tegal Alang-Alang yang
kemudian disebut Lemah Wungkuk. Pada masa Raden Walangsungsang berubah
lagi namanya menjadi Caruban. Purwaka Tjaruban Nagari juga menjelaskan bahwa
Cirebon berasal dari kata “Caruban”“Carbon” “Cerbon”“Cirebon”, berarti
campuran. Pada saat itu, Cirebon sudah didiami oleh penduduk dari berbagai
bangsa dan juga agama yang majemuk. Pekerjaan penduduknya juga bervariatif.
Sementara dalam definisi lain, Cirebon secara etimologis berasal dari dua kata
bahasa Sunda”Ci” yang berarti air, dan “Rebon” adalah sejenis udang kecil-kecil
yang merupakan bahan baku untuk membuat terasi.76
Terdapat banyak pelafalan dan cara penulisan kata Cirebon. Pires misalnya,
menyebut Cirebon dengan kata “Choroban”.77
Berbeda dengan Pires, orang-orang
Belanda78
pada masa awal kehadirannya di Nusantara menyebut Cirebon dengan
kata “Charaboan”, yang selanjutnya pada masa akhir menjadi “Tjerbon dan
Cheribon”. Masyarakat setempat menyebutnya “Nageri Gede” (Negara
Agung/Besar). Kata ini kemudian berubah pengucapannya menjadi “Garage” dan
berubah lagi menjadi “Grage”. Grage berasal dari kata “glagi” yang berarti udang
kecil yang telah kering. Negeri Cirebon juga sering disebut sebagai “puser bumi”
atau “puser jagad” oleh para Wali Sango karena letaknya yang berada di tengah
Pulau Jawamenjadi pusat penyiaran Islam untuk wilayah tanah Sunda.79
Wilayah yang sekarang dikenal Cirebon sebenarnya berasal dari wilayah kecil
di pesisir pantai utara pulau Jawa, yang bernama Tegal Alang-Alang atau Lemah
Wungkuk. Orang yang membangun wilayah ini adalah Pangeran Cakrabuana alias
Ki Somadullah. Namun demikian, ia bukan orang pertama yang berada di wilayah
74
R. A. Kern & H. Djajadiningrat, Masa Awal Kerajaan Cirebon, (Jakarta: Bhratara,
1974), h. 9. 75
Naskah ini ditulis oleh Pangeran Arya Carbon pada tahun 1720 M. 76
Atja, Purwaka Caruban Nagari…, h. 28. 77
A. Cortesao, The Summa Oriental of Tome Pires, (London: Hakluyt Society 1994),
h. 67. 78
Dalam tulisan-tulisan Belanda, misalnya, Dagh Register, mencatat nama “Cirebon”
sekurang-kurangnya ditulis dan dieja dalam 25 cara. Kemudian dari cara penulisan yang
banyak itu, pada abad ke-18 terwujud cara penulisan “Cheribon”. Lihat Kern &
Djajadiningrat, Masa Awal Kerajaan..., h. 13. 79
Atja, Carita Purwaka Caruban…, h. 28-29.
89
ini karena sebelumnya sudah ada Ki Danusela yang bergelar Ki Gedheng Alang-
Alang yang kelak menjadi Kuwu pertama dan menjadi mertuanya. Usaha Ki
Somadullah ini tidak terlepas dari perintah gurunya Syekh Nurjati, seorang muballig
Islam yang pernah singgah di Pelabuhan Muara Jati.80
Menurut sumber tradisional, semula di daerah pesisir Cirebon terdapat tiga
pelabuhan yaitu Muara Jati, Japura dan Singapura. Pada awalnya, ketiga pelabuhan
tersebut berada di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh. Wilayah Amparan Jati dengan
Muara Jatinya merupakan pelabuhan internasaional pada saat itu. Dalam
perkembangannya, wilayah Amparan Jati merupakan bagian dari Lemah Wungkuk.
Selanjutnya pelabuhan internasional juga berpindak ke Lemah Wungkuk. Wilayah
Lemah Wungkuk semakin lama semakin luas dan akhirnya berubah nama menjadi
Caruban atau Cerbon atau Cirebon pada masa Ki Somadullah alias Pangeran
Cakrabuana. Setelah Cirebon berkembang, pelabuhannya menjadi ramai dengan
kegiatan perdagangan, dan termasuk menjadi salah satu pusat pelabuhan di pantai
utara Jawa. Ada empat faktor yang memengaruhi perkembangan Cirebon sebagai
pelabuhan penting. Pertama, letak geografisnya yang strategis, pelabuhan Cirebon
berada pada lokasi berbentuk teluk, sehingga kondisi pelabuhan terlindungi dari
gelombang air pasang laut. Kedua, pelabuhan Cirebon terletak di bagian tengah
pesisir utara Pulau Jawa, dan cukup jauh dari pelabuhan lain seperti Jepara, Tuban,
Surabaya yang berada di sebelah timur Pulau Jawa dan Sunda Kelapa serta Banten
di sebelah barat Pulau Jawa. Ketiga, pantai Cirebon mudah didatangi oleh perahu,
bahkan dapat dimasuki oleh kapal berukuran besar. Keempat, hubungan antara
pelabuhan dengan daerah pedalaman berlangsung lancar, baik melalui sungai
maupun darat. Sungai-sungai itu di antaranya Sungai Krian, Sungai Cimanuk, dan
Sungai Cilosari.81
Secara historis, status Cirebon yang dikenal sekarang sebelum dipimpin oleh
Pangeran Cakrabuana, sekitar abad ke 14 dan awal abad ke 15 adalah wilayah yang
terpecah-pecah dan terbagi ke dalam beberapa nagari. Nagari-nagari tersebut
meliputi Surantaka,82
Singapura,83
Japura, Wanagiri Rajagaluh, dan Talaga. Secara
politik, nagari-nagari tersebut dipimpin atau dikuasai oleh penguasa yang dikenal
dengan sebutan Ki Gedeng. Misalnya, Wanagiri yang nantinya menjadi Ibu kota
Cirebon Girang di pegang oleh Ki Gedeng Kasmaya, Ki Gedeng Sedhnag Kasih
memegang Surantaka dan Amparan Jati, Ki Gedeng Surawijaya Sakti memegang
Singapura yang dikemudian hari diserahkan kepada Ki Gedeng Jumajan Jati atau Ki
80
Adeng, dkk., Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra, (Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h. 21; Rosyidin, dan A. Syafaah, A.
Keragaman Budaya Cirebon…, h. 25. 81
Rosyidin, dan A. Syafaah, A. Keragaman Budaya Cirebon…, h. 25-26. 82
Wilayah ini letaknya berada di sebelah utara 4 Km dari Amparan Jati (Makam Sunan
gunung Jati) 83
Singapura berada kurang lebih 4 km. dari sebelah utara Giri Aparan Jati, sebalah
utara berbatasan dengan Nagari Surantaka, sebelah barat berbatasan dengan Nagari
Wanagiri, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Japura, dan sebalah timur berbatasan
dengan laut Jawa (teluk Cirebon). Pusat pemerintahanya terletak di Desa Sirnabaya
sekarang. Lihat Tim Penulis, Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra, (Jakarta:
Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, 1998), h. 48.
90
Gedeng Tapa. Meski secara sekilas wilayah-wilayah ini terpisah namun nagari
tersebut pada dasarnya tunduk dan patuh pada Kerajaan Sunda/Galuh, sebab semua
Ki Gedeng secara genealogis memliki ikatan darah dan kekerabatan.84
Sungai-sungai di Cirebon ketika itu digunakan sebagai sarana lalu lintas untuk
perahu dan kapal yang cukup besar. Hal ini seperti disaksikan oleh Tome Pires pada
tahun 1513. Dalam catatan perjalannya, ia menyebutkan bahwa Cirebon adalah kota
pelabuhan yang ramai oleh kegiatan perdagangan. Pelabuhan Cirebon merupakan
salah satu pelabuhan ramai di Pulau Jawa yang sering didatangi oleh para pedagang
dari berbagai negara, seperti Arab, India dan Tiongkok. Dengan semakin ramainya
pelabuhan Cirebon, ada sejumlah pedagang pribumi dan asing yang tinggal di
sekitar pelabuhan, salah satunya adalah saudagar Asing Pate Quedir, yang semula
tinggal di Malaka. Pelabuhan Cirebon menjadi salah satu tempat untuk mengeskpor
berbagai hasil komoditi hasil bumi seperti terasi, ikan, daging, padi, beras, sayur
dan buah-buahan, serta tarum dan kayu yang baik untuk pembauatan kapal.85
Cirebon adalah salah satu kota pantai yang terletak di ujung timur pantai utara
Tatar Sunda yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional pada masanya. Pada
awalnya Cirebon ini merupakan sebuah pemukiman nelayan yang tidak berarti.
Kemudian berkembang menjadi pedukuhan atau desa yang bernama Dukuh Tegal
Alang-Alang berada kurang lebih 5 km di sebalah utara Kota Cirebon sekarang.
Berkembangnya Cirebon sebagai pelabuhan yang ramai didukung oleh beberapa
faktor kondusif yang dibutuhkan oleh pelabuhan-pelabuhan besar pada waktu itu.
Pertama, Cirebon dapat bertindak sebagai pangkalan tempat para pelaut membeli
bekalair tawar, beras dan sayur untuk persediaan dalam perjalanan. Kedua,
Cirebon menjadi tempat bermukimnya para pedagang besar yang bertindak sebagai
pemilik modal, sedangkan bandar Cirebon dijadikan sebagai tempat penyimpanan
barang-barang perdagangan.86
Dengan demikian, harus diakui Cirebon merupakan
pangkalan penting, dan memiliki akses perdagangan dan pelayaran antarbangsa.
Lokasinya berada di antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, turut menjadikannya
sebagai jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda sehingga terciptanya suatu
kebudayaan yang khas. Di samping itu, Cirebon menyimpan beberapa warisan
budayatradisi dan kesenian, serta warisan fisik sebagai hasil perpaduan antara
kebudayaan lokal dan asingArab, India, Tiongkok dan Eropa.
Dalam bidang pemerintahan Cirebon merupakan salah satu dari Kerajaan Islam
yang ada di Nusantara. Kerajaan ini dikenal dengan nama Kesultanan Cirebon. Raja
pertama Kesultanan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati. Dalam pemerintahannya, ia
menerapkan sistem pemerintahan yang tertata rapih sehingga para penerusnya dapat
meneruskan dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Beberapa sultan
setelah Sunan Gunung Jati adalah, Pangeran Pasarean, Panembahan Ratu, Sultan
Sepuh dan Sultan Anom.
84
N. H. Lubis, A. Sulaeman, Y. Munaf, & M. R. Razman, “Islamization of the Sunda
Kingdom”. International Information Institute (Tokyo), Information, vol. 21, no. 4, 2018, h.
1349-1357.; Tim Penulis, Kota Dagang Cirebon…, h. 48. 85
Cortesao, The Summa Oriental…, h. 27. 86
Cortesao, The Summa Oriental…, h. 27.
91
Pada tahap selanjutnya, Cirebon mengalami beberapa perubahan dengan
terpecahnya menjadi empat kesultanan dengan masing-masing keraton, yaitu: 1)
Keraton Kasepuhan. 2) Keraton Kanoman. Keraton ini didirikan oleh Pangeran
Muhammad Badruddin/Pangeran Kertawijaya (Sultan Anom 1) sekitar tahun 1678.
3) Keraton Kacirebonan adalah pecahan dari Keraton Kanoman yang luasnya
sekitar 2.5 hektar, dan Sultan Carbon adalah sebagai Amirul Mukminin. 4) Keraton
Keprabonan, berdiri tahun 1696 dan dipimpin oleh Pangeran Raja Adipati
Keprabon.87
Di abad ke-18, keadaan masyarakat Cirebon semakin memburuk ketika berada
di bawah pemerintahan kolonial. Masalah yang dihadapi cukup banyak, utamanya
dalam bidang sosial dan ekonomi. Penjualan diri untuk menjadi budak meningkat
tajam, wabah penyakit dan kelaparan menyerang masyarakat Cirebon pada tahun
1719, 1721, 1729, 1756, 1757, 1773, 1775, 1776, 1792 dan 1812. Tindakan
kompeni yang semena-mena terhadap rakyat dan kesengsaraan yang dialami
menyebabkan timbulnya pemberontakan, kekacauan terjadi di mana-mana selama
bertahun-tahun. Puncak amarah rakyat Cirebon terjadi pada tahun 1802 berupa
gerakan perlawanan rakyat menentang Belanda beserta kaki tangannya, yaitu etnis
Tionghoa. Akibat perlawanan rakyat Cirebon, banyak etnis Tionghoa yang terbunuh
dan diusir dari daerah Cirebon dan sekitarnya.88
Secara historis, sampai awal abad ke-20 pemerintah Belanda melakukan
eksploitasi dengan mengadakan pembukaan perkebunan tebu dan mendirikan pabrik
gula di wilayah Karesidenan Cirebon. Hak kepemilikan tanah masyarakat tentunya
semakin terampas dan masyarakat berada dalam kemiskinan. Namun, pada
perjalanannya eksploitasi terhadap berbagai daerah di Nusantara berkurang seiring
dengan munculnya politik etis akibat desakan dan kritikan dari partai liberal
Belanda bersamaan dengan pernyataan keprihatinan dari pihak pemerintahan
Belanda terhadap kesejahteraan rakyat pribumi (Indonesia).89
Sejak Cirebon dijadikan Kota Praja (Gemeente) atau Ibu kota Karesidenan
Cirebon pada 1 April 1906. J. H. J. Sigal sebagai Asisten Residen di Cirebon
mengajak seluruh warga Kota Cirebon dan sekitarnya untuk sama-sama memajukan
pemerintahan kota, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan
pribadi, meningkatkan bidang kesenian dan ilmu pengetahuan, dan menyediakan
fasilitas umum yang mudah dan cepat. Pemerintah Hindia Belanda memandang
Kota Cirebon sebagai daerah penting dan strategis untuk dijadikan sebagai pusat
pemerintahan dan daerah industri di Jawa Barat bagian timur. Sejalan dengan itu,
perkembangan perekonomian dan industri gula semakin berkembang. Pemerintah
Hindia Belanda meningkatkan status Kota Cirebon menjadi Stadgemeente yaitu
kota yang memiliki otonomi luas dalam pengembangan wilayahnya dan dalam
mengatur rumah tangganya sendiri. Sejak itu Cirebon mengalami proses
87
D. R. Indika, “Ingsun Titip Tajug Lan Fakir Miskin”, dalam Pembangunan dengan
Berbasiskan Budaya dan Kearifan (Pengembalian Citra Keraton sebagai Pusat
Kebudayaan dan Ekonomi Cirebon, ISEI Economic Review, vol II, no. 1, 2018, h. 1-7. 88
Susanti, “Pengaruh Kolonial…,” h. 274-288. 89
Imas Emalia, “Geliat Ekonomi Kelas Menengah Muslim di Cirebon: Dinamika
Industri Batik Trusmi 1900-1980”. Al-Turas, vol. XXIII, no. 2, 2017, h. 211-230.
92
modernisasi dan industrialisasi sebagai pusat pengembangan perekonomian
perkebunan, khususnya tebu. Dengan demikian, Cirebon banyak mengalami
perubahan, baik dari segi fisik perkotaan maupun pola perekonomian masyarakat.90
Perkembangan masyarakat Cirebon dari sisi sosial-ekonomi tidak dapat
dipisahkan dari sarana dan prasarana, termasuk transportasi. Keberadaan Cirebon
yang dilintasi sugai-sungai kecilmengalir ke laut mengakibatkan transportasi air
menjadi sangat dibutuhkan. Ada beberapa sungai yang saling terhubungsungai
Krian, sungai Cimanuk dan sungai Cilosarisemuanya dapat dilalui oleh perahu
dan kapal kecilmenjadi penghubung antara daerah pedalaman dan daerah pesisir,
baik yang berkaitan dengan aktivitas sosial maupun ekonomi. Pires dalam
catatannya menyebutkan bahwa beberapa sungai di Cirebon dapat dilalui oleh
perahu atau junk sejauh kira-kira 3 mil. dari pesisir ke arah hulu sungai.
Transportasi laut membantu para petani untuk mengangkut hasil pertanian dan hasil
hutan yang laku dijual di pasaran yang berada di pesisir. Dengan demikian, moda
transportasi laut ketika itu mendorong mobilitas sosial, baik di wilayah pusat
kerajaan maupun dari dan ke wilayah pedalaman.91
Meningkatnya pertanian, khususnya padi di daerah pedalaman menjadikan
Cirebon sejak abad ke-15 hingga abad ke-17 sebagai produsen utama beras di Pulau
Jawa, di samping Rembang, Mataram, dan Banten. Hasil tani masyarakat
pedalaman menjadi potensi ekonomi dalam menunjang kegiatan ekonomi di
Cirebon. Tidak heran, pedalaman Cirebon sebagai penghasil beras diakui oleh
pemerintah kolonial Belanda. Dalam sumber Belanda diberitakan bahwa awal abad
ke-1, Cirebon menghasilkan beras berkualitas baik, minyak kelapa, kacang-
kacangan, bawang putih, dan lain-lain. Bahkan, ketika penjajah Belanda di Batavia
kekurangan beras (Agustus 1617), para kompeni mendatangkan beras dari Cirebon.
Pada pertengahan tahun 1619 hampir tiap hari banyak kapal dari Cirebon datang ke
pelabuhan Sunda Kalapa dengan berbagai macam muatan.92
Hingga saat ini, Cirebon adalah sebuah kota yang memiliki daya tarik
tersendiri dibanding kota lainnya. Secara geografis Cirebon merupakan daerah
pesisir yang dijuluki sebagai kota warisan kesultanan dan warisan Wali Songo.
Banyak budaya yang hadir di tengah masyarakat Cirebon merupakan warisan
kesultanan dan warisan para wali. Pernyataan ini dipandang objektif berdasarkan
bukti-bukti dan data sejarah yang ada,93
yakni Cirebon memiliki wisata budaya
berupa keraton-keraton yang bersejarah, wisata ziarah, kesenian tari topeng, musik
tarling dan batik Trusmi. Keraton dan tinggalan budaya lainnya seyogyanya
menjadi landmark yang dapat menjadi ikon daerah yang jika dikembangkan
menjadi potensi ekonomi tidak hanya buat masyarakat sekitar tetapi juga
pemerintah daerah setempat. Tinggalan-tinggalan budaya tersebut perlu dikelola
90
Emalia, “Geliat Ekonomi Kelas…, h. 211-230. 91
S. Zuhdi, Hubungan Pelabuhan Cirebon dengan Daerah Pedalaman: Suatu Kajian
dalam Kerangka Perbandingan dengan Pelabuhan Cilacap 1880-1940, (Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), h. 119. 92
Susanti, “Pengaruh Kolonial…,” h. 274-288. 93
Emalia, “Geliat Ekonomi Kelas…, h. 211-230.
93
dengan manajemen yang baik dan profesional sehingga menjadi wahana yang dapat
menjadi kebanggan baik dalam skala lokal, regional maupun internasional.
Perekonomian sebuah daerah akan dipengaruhi oleh letak geografis yang
strategis dan sumber daya alam yang dimilikinya. Perekonomian di Cirebon
didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, restoran,
sektor pengangkutan, komunikasi dan sektor jasa. Kota Cirebon termasuk kota yang
cepat bertransformasi dari tatanan ekonomi tradisional yang bertumpu pada sektor
yang mengandalkan sumber daya manusia seperti industri pengolahan, perdagangan
dan jasa. Sektor industri dan perdagangan sedang mengalami perkembangan yang
pesat dibanding sektor lainnya. Pertumbuhan jumlah perusahaan dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan, dan hal ini berimplikasi pada pertambahan lapangan kerja
bagi masyarakatnya.94
Namun, di tengah kemodernan dan arus globalisasi,
pembangunan Kota Cirebon dilakukan dengan tetap berbasiskan budaya dan
kearifan lokal “ingsun titip tajug lan fakir miskin” untuk dapat mengembalikan
Cirebon sebagai kota historis dan demi kemandirian kesultanan di masa yang akan
datang.95
2. Cirebon dalam Lintas Dagang
Cirebon sebagai bandar niaga berperan dalam perdagangan internasional,
kedatangan kapal-kapal asing di Cirebon memperjelas keterkaitan Cirebon dalam
jaringan internasional. Dalam beberapa catatan dari sumber Portugis, yakni Tome
Pires menyebutkan bahwa Cirebon adalah sebuah pelabuhan yang indah dan selalu
ada empat sampai lima kapal yang berlabuh. Hasil bumi yang dihasilkan selain
beras adalah bahan makanan lainnya. Pires juga mencatat adanya kegiatan
perdagangan di wilayah Jawa Barat, sedangkan beberapa pelabuhan di antaranya
dikuasai oleh Kerajaan Sunda yakni Banten, Pontang, Cigede, Tanara, Calap dan
Cimanuk. Selain itu, ia menyebutkan ada beberapa pelabuhan di wilayah Jawa
yaitu Cirebon, Japura, Tegal Semarang, Demak, Jepara, Rembang, Tuban, Giri dan
Surabaya. Dalam catatan Pires, mata uang yang digunakan dalam transaksi
perdagangan atau jual beli adalah mata uang Tiongkok. Bentuk mata uang tersebut
yakni berlubang di bagian tengah, dan di sampingnya terdapat jenis mata uang
lainnya.96
Setelah dibangun oleh Pangeran Walangsungsang, pelabuhan Cirebon semkin
ramai dan baik untuk akses perhubungan laut antara Persia, Mesir, Arab, Tiongkok,
dan Campa serta menghubungkan dengan beberapa pelabuhan lain. Perkembangan
pelabuhan Cirebon juga didukung dengan ekspansi Kerajaan Islam Cirebon untuk
menguasai pelabuhan-pelabuhan di wilayah Pajajaran. Setelah Banten dikuasai
(tahun 1526) dan Sunda kelapa (1527), maka seluruh pesisir pantai utara Jawa Barat
dalam kekuasaan Kerajaan Islam. Akibat politik ini, jaringan perdagangan
94
Indika, “Ingsun Titip Tajug…, h. 1-7. 95
Indika, “Ingsun Titip Tajug…, h. 1-7. 96
Tome Pires, Summa Oriental, terj. Sri Margana, (Yogyakarta: Penerbit Ombak,
2014), h. 237.; I. M. Johan, Penelitian Sejarah Kebudayaan Cirebon dan Sekitamya Antara
Abad XV-XIX: Tinjauan Bibliografi, dalam Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra, (Jakarta:
Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia, 1996), h. 10.
94
internasional yang sedang tumbuh dan berkembang terbentang dari Demak, Cirebon
hingga Banten.97
Kota-kota pelabuhan mempunyai peran sebagai pusat ekonomi di setiap
wilayahnya. Hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai jalur ekspor dan impor hasil-
hasil bumi dari daerah pedalaman yang terpencil yang dihubungkan dengan jalan
sungai maupun darat, sehingga dimungkinkan membutuhkan adanya kebutuhan jasa
angkutan. Sudjana mengatakan setidaknya ada tiga indikator dasar suatu pelabuhan
yang harus berlangsung dan berlanjut, yaitu: (1) adanya hubungan antara pasar
dunia dengan pasar domestik; (2) adanya hubungan antara pelabuhan dengan daerah
pedalaman sehingga terbentuknya jalur atau akses transportasi, serta terbentuknya
pusat-pusat pengumpulan barang dagangan; dan (3) hubungan antara kegiatan
pelabuhan dengan pembentukan kota pelabuhan itu sendiri.98
Tiga indikator tersebut
dapat dilihat di Cirebon, sebagai kota pelabuhan telah menjadi tempat untuk
menghubungkan dua dunia yaitu daratan dan lautan. Sementara dari segi ekonomi,
pelabuhan Cirebon juga berfungsi sebagai tempat menampung atau gudang barang
dagangan dari wilayah pedalaman untuk didistribusikan dan dijual ke tempat-tempat
lain yang membutuhkan. Selain itu, pelabuhan Cirebon berfungsi sebagai tempat
penampungan barang-barang dari tempat lain yang tidak dihasilkan dari wilayah
pedalaman yang sangat dibutuhkan seperti produk-produk kerajinan (keramik, kain
dan sebagainya).
Oleh karena itu, dengan adanya kebutuhan yang timbal balik membuat
pelabuhan dan pedalaman menjadi posisi yang saling membutuhkan dan antara satu
dengan lainnya saling menopang. Dalam konteks ini sarana dan prasarana
transportasi dibangun untuk memudahkan arus perdagangan barang, baik dari
pelabuhan maupun menuju pelabuhan. Ekajati mengatakan bahwa hubungan ke
daerah pedalaman terjalin melalui sungai dan jalan darat. Sungai di Cirebon
berperan sebagai jalan atau lalu lintas yang dapat dilayari perahu atau kapal ke arah
pedalaman, disaksikan Pires di tahun 1513. Mungkin sungai yang dimaksud adalah
sungai Krian (sekarang) yang dapat dilayari sampai Cirebon Girang, Sungai
Cimanuk di sebelah utara dan Sungai Cilosari di daerah pedalaman wilayah
Cirebon.99
Dengan bertambahnya para pedaganag dari mancaegara yang masuk ke
pelabuhan Cirebon ikut membuat barang-barang yang berasal dari mancanegara
masuk ke wilayah Cirebon. Barang-barang itu dibutuhkan masyarakat pedalaman
dikarenakan mereka tidak memproduksi barang-barang seperti logam besi, emas
dan perak serta tekstil halus (sutera dan keramik). Di samping barang-barang yang
menjadi kebutuhan masyarakat daerah pelabuhan seperti garam, terasi dan ikan
97
Uka Tjandrasasmita, Bandar Cirebon dalam Jaringan Pasar Dunia, (Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), h. 13. 98
T. D. Sudjana, Pelabuhan Cirebon Dahulu dan Sekarang, (Jakarta: Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), h. 14. 99
E. S. Ekajati, dkk, Sejarah Cirebon Abad Ketujuh Belas, (Bandung: Kerjasama
Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat dan Universitas Padjajaran, 1991), h. 45.
95
asin.100
Mengenai situasi perdagangan barang yang diperjual belikan di pelabuhan
Cirebon dapat dilihat pada catatan Pires, yaitu:
“The land of Cherimon is next to Sundai its lard is called Labe Uca. He is
vassal of Pate Rodim, lard of Demak. This Cherimon has a good port and there
must be three or four junks there. It has a deal of rice and many foodstuffs: it
must have as many as ten small lancaras, they say that it has not so many now.
This place cherimon must have up to a thousand inhabitats. Pate Quedir the
one who revolted in upeh lives in this place cherimon. There must be five or six
merchants in cherimon as great as Pate Quedir, but they all and the lord of
cherimon do honour to Pate Quedir, because they hold him to be a bold
merchant and a knight.101
Dari catatan Pires di atas, dapat diketahui bahwa ketika Pires datang ke
Cirebon, daerah ini memiliki pelabuhan yang bagus dan dan ramai dikunjungi oleh
para pedagang. Kapal-kapal yang berlabuh di sana antara lain 3 atau 4 junk. Pires
mencatat junk dan lancara sebab pada waktu itu berlaku tradisi menilai sebuah
pelabuhan dari kemampuan pelabuhan tersebut dilabuhi kapal besar (junk) dan
lancara. Sementara kapal-kapal ukuran kecil yang berlabuh tidak dicatat Pires,
tetapi dengan menganalisis situasi perdagangan ketika itu, menurut penulis kapal-
kapal tersebut dimungkinkan lebih banyak. Ramainya aktivitas perdagangan di
pelabuhan Cirebon juga dapat dilihat dari jumlah penduduknya mencapai 1000 jiwa
dengan lima atau enam saudagar, salah satunya yaitu Pate Quedir salah seorang
saudagar yang cerdik, berani dan dihormati oleh masyarakat. Di samping itu, dapat
diketahui bahwa komoditi Cirebon adalah berupa beras dan bahan makanan lainnya,
namun Pires tidak menyebutkan nama-nama komoditas lainnya. Barang-barang lain
yang tidak disebutkan adalah barang hasil jual beli dari negeri-negeri lain ke
wilayah Cirebon. Padahal setiap harinya banyak perahu yang masuk ke Pelabuhan
Muara Jati dari Jawa Timur, Madura dan Palembang.102
Hal tersebutlah yang
kemudian membuat pelabuahn Cirebon ramai dikunjungi oleh para pedagang.
Pelabuhan Muara Jati mengalami perubahan dan perbaikan serta
penyempurnaan bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai fasilitas pelayaran
seperti Mercusuar yang dahaulu dibuat oleh Ki Ageng Tapa yang dibantu oleh etnis
Tionghoa. Selain itu, dibagun pula bengkel sebagai tempat untuk memperbaiki
perahu yang rusak dengan memanfaatkan etnis Tionghoa ahli pembuat junk yang
dahulu dibawa oleh Cheng Ho. Sementara dalam rangka merealisasikan Cirebon
sebagai kota pelabuhan, Sunan Gunung Jati melakukan pembangunan pangkalan
perahu yang terletak di sebelah tenggara Keraton Cirebon tepatnya di tepi sungai
Kriyan. Pangkalan perahu ini dilengkapi dengan gapura yang disebut Lawang
Sanga, bengkel perahu, istal kuda kerajaan dan beberapa pos pengamanan.103
Untuk menunjang sarana transportasi dibangunlah sarana transportasi sebagai
penunjang pelabuhan, baik akses transportasi darat maupun laut. Pembangunan
100
Tim Penulis, Kota Dagang Cirebon…, h. 54. 101
Cortesao, The Summa Oriental…, h. 27. 102
Dartano, Penyebaran Agama Islam di Cirebon dan Sekitarnya antara Tahun 1470-
1570 M, (Universitas Indonesia, 1991), h. 18 103
Susanti, “Pengaruh Kolonial…,” h. 274-288.
96
akses jalan darat dimulai dari alun-alun Keraton Pakungwati ke arah pelabuhan
Muara Jati. Pembangunan akses jalan ini bertujuam agar para pedagang asing atau
para utusan dari kerajaan lain dapat dengan mudah masuk ke pelabuhan Muara Jati,
atau memudahkan bagi siapa saja yang ingin bertemu dengan Sunan Gung Jati,
khususnya dalam urusan pemerintahan. Selain itu, dibentuk juga pasukan untuk
menjaga dan memlihara keamanan yang diberi nama Pasukan Jagabaya dengan
jumlah dan kualitas yang memadai. Pasukan ini ditempatkan di pusat kerajaan dan
tempat-tempat yang masuk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon.
Terkait komoditi barang yang diekspor dari Cirebon, naskah Negara
Kertabumi menggambarkan dan membantu menjelaskan jenis barang-barang
tersebut. Dalam naskah itu disebutkan bahwa:
“Pada tahun 1337 Saka (1415M), Muhara Jati kedatangan armada Cina yang
dipimpin oleh Cenhuwa (laksamana), Mah-wan (juru tulis), Ong Keng-Hong
(juru mudi), Kung Way-Ping (panglima), dan Pey-Sin (juru tulis). Mereka
semua adalah utusan Maharaja Cina Yuwang-Lo (Yung-Lo) dari wangsa
Ming. Dalam gerombolan itu terdapat beberapa orang pembesar kerajaan
Wilwatika yang menjadi duta di Swarnabhumi. Di Muhara Jati armada itu
berhenti mendapatkan perbekalan, atas persetujuan kedua belah pihak, di
Muhara Jati didirikan sebuah menara sebagai imbalan, pihak Cina
mendapatkan perbekalan yang diperlukan berupa garam, terasi, beras tumbuk,
rempah-rempah dan kayu jati”.104
Barang-barang komoditas yang didatangkan ke Cirebon dapat diketahui dari
keterangan yang terdapat dalam cerita Purwaka Caruban Nagari seperti logam besi,
perak, emas, sutra, dan keramik halus.105
Barang-barang yang diperjualbelikan di
pelabuhan Cirebon pasti sama dengan barang-barang yang diperjualbelikan di
pelabuhan Kerajaan Sunda mengingat pelabuhan Cirebon sezaman. Mengenai
barang-barang komoditi yang ada di pelabuhan Kerajaan Sunda, Cortesao menulis
pernyataan Pires bahwa komoditi Kerajaan Sunda yang terpenting adalah beras
(mencapai 10 junk setahun), lada (1000 bahar setahun), dan kain tenun yang
diekspor ke Malaka. Sementara sebagai barang import bagi Kerajaan Sunda adalah
tekstil halus dari Cambay, dan kuda dari Pariaman sebanyak 4.000 ekor pertahun
yang diperguankan untuk angkatan perang dan berburu.106
Dalam hal alat tukar menukar yang dipergunakan, pedagang Tionghoa
mempunyai peran dominan sebagaimana ditunjukkan bahwa dipergunakannya mata
uang Tiongkok sebagai alat tukar menukar utama di Jawa.107
Uang Tiongkok
didatangkan langsung dari Tiongkok, bahkan impor mata uang Tiongkok terus
berlangsung sampai masa VOC.108
Bukti-bukti lain yang memperkuat bahwa uang
Tiongkok dipergunakan adalah terdapatnya keramik Tiongkok, kain sutera,
104
Atja, Nagarakretabumi, (Bandung: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan
Sunda (Sundanologi), Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1986), h. 37. 105
Atja, Carita Purwaka Caruban…, h. 56. 106
Cortesao, The Summa Oriental…, h. 169. 107
Sunardjo, Meninjau Sepintas Panggung…, h. 45. 108
Rosyidin, Kerajaan Cirebon, h. 67.
97
kelenteng dan vihara di setiap pelabuhan yang ada di Jawa. Selain mata uang
Tiongkok, alat tukar menukar yang digunakan untuk jalinan perdagangan di Pulau
Jawa adalah uang Portugis yang dikenal dengan nama crusados, uang malaka
disebut calais dan uang lokal Jawa yang diberi nama tumdaya atau tail.109
Nilai mata uang yang dipergunakan oleh para penduduk Cirebon tidak jelas
mata uang mana yang dijadikan standar. Ada beberapa perbandingan nilai dalam
mata uang itu, misalnya mata uang Tiongkok yang memilki nilai kecil diberi lubang
di tengahnya, sehingga mata uang tersebut dapat diikat mencapai seratus buah.
Setiap ikatan memuat 100 keping uang logam yang setara nilainya dengan lima
calais Malaka. Sementara mata uang dengan nilai besar terdapat nilai mata uang
emas yantg nilainya sama dengan 3000 calais atau 9 crusados.110
Akan tetapi
sebelum itu, di Nusantara telah dikenal bentuk uang berupa koin emas dan koin
perak pada masa Hindu. Demikian juga pada masa awal Islam, terutama di daearah-
daerah pantai yang menjadi jalur perdagangan dikenal beberapa jenis uang seperti di
Banten dikenal jenis uang berupa koin tembaga dan perak, Sumenep berupa bahan
celup yang dioleskan pada kain yang sudah dipakai, Cirebon dikenal dengan uang
yang terbuat dari takaran kecil timah yang disebut picis dan sebagainya.111
Mengenai kondisi obyektif pelabuhan Cirebon yang menjadikannya sebagai
kerajaan maritim dan pelabuhan besar yang ramai dapat dilihat sebagaimana dalam
catatan Pires bahwa pada tahun 1514 Cirebon merupakan pelabuhan yang baik,
setiap waktu ada 3 atau 4 junk (sejenis perahu besar) yang berlabuh di sana,
sedangkan lancara (sejenis perahu yang laju jalannya) hanya berlabuh. Junk adalah
alat transfortasi yang trekenal di mana-mana, dan hanya dapat menyusuri sungai
yang mengalir sejauh 9 mil.112
Junk juga dijadikan sebagai ukuran untuk
menetukan besar kecilnya sebuah pelabuhan, selain itu dipakai sebagai alat
pengukur kekuatan suatu kerajaan. Semakin banyak junk yang dimiliki oleh sebuah
kerajaan, maka kerajaan itu dinilai sebagai kerajaan besar. Sumber lain mengatakan
bahwa pada masa itu junk para saudagar Tionghoa sangat terkenal. Tjiptoatmojo
mengutip pendapat Eduard Sebberg mengatakan bahwa junk Tiongkok menarik
perhatian, tinggi haluan dan buritannya tidak sama, sedangkan bagian tengahnya
rendah. Nampak di atas buritan terdapat sejumlah rumah-rumah kecil dan cukup
mencolok juga umbul-umbul yang berwarna coreng moreng, kedua layarnya lebar
dan tebal terbuat dari sebangsa daun rumput yang diayam.113
Adapun soal perahu
lancara termasuk ke dalam jenis perahu muatan barang yang berukuran besar. Pires
mencatat mengenai perdagangan Kerajaan Sunda dan Malaka, barang-brang
109
Cortesao, The Summa Oriental…, h. 70. 110
Tim Penulis, Kota Dagang Cirebon…, h. 58. 111
Tim Penulis, Kota Dagang Cirebon…, h. 59. 112
E. S. Ekajati, (ed.), Masyarakat Sunda dan Kebudayaannya, (Jakarta: Girimukti
Pasaka, 1984), h. 90. 113
F. A S. Tjiptoatmojo, “Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura Abad XIX sampai
Medio Abad XIX”. (Disertasi Doktoral Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM Yogyakarta,
1983), h. 91.
98
komoditas Sunda diangkut dengan lancara, yaitu sejenis kapal yang berkapasitas
sampai 150 ton.114
Dengan posisinya sebagai kerajaan maritim, Cirebon menjadikan perahu tidak
hanya sebagai sarana transportasi dagang tetapi digunakan juga sebagai armada
perang. Armada perang Cirebon pernah dikirim ke Demak untuk membantu dalam
upaya menumpas armada Prabu Rangga Premana (Ratu Supiturung). Pada saat itu
pasukan Cirebon bergabung dengan pasukan Banten, Sunda Kelapa dan Demak
yang semuanya berjumlah 3007 armada perahu.115
Karena semakin ramainya
pelabuhan Cirebon, masyarakat sekitar pelabuhan mempunyai pekerjaan baru
sebagai pengrajin atau pembuat perahu. Sebenarnya teknologi pembuatan perahu
sudah dikembangkan oleh para penduduk di sekitar pesisir pantai dan di daerah
yang ada sungainya. Perahu selain digunakan sebagai alat transportasi juga
mempunyai fungsi dan peranan sosial yang penting, baik sebagai sarana untuk mata
pencaharian maupun sebagai sarana kekuatan politik dalam bentuk armada perang.
Mata pencaharian sebagai nelayan atau pelaut merupakan salah satu sumber
daya yang dimiliki masyarakat Cirebon. Para nelayan ketika itu memiliki arti
penting bagi Kerajaan Cirebon, selain sebagai tenaga dalam perolehan hasil laut dan
perdagangan di laut, juga berperan sebagai penjaga perairan pantaiberpatroli di
selat dan menjaga keamanan para pedagang yang akan singgah di pelabuhan dan
berkunjung ke Kerajaan Cirebon. Dengan bertambahnya wilayah kekuasaan
Cirebon yang mencakup beberapa daerah pedalaman, ikut mengubah corak
kehidupaan kerajaan dari yang semula bercorak kerajaan maritim berubah menjadi
kerajaam maritim agraris. Kehidupan bercorak maritim ditunjukan oleh masyarakat
nelayan dengan meningkatnya kegiatan perdagangan di wilayah kawasan
pelabuhan. Sementara perkembangan kehidupan agraris ditandai dengan
meningkatnya kegiatan pertanian yang banyak menghasilkan komoditas hasil bumi.
3. Cirebon sebagai Basis Syiar Islam
Gerakan islamisasi adalah bagian dari sejarah Nusantara yang fenomenal.
Kedatangan Islam di Nusantara yang kemudian diikuti dengan gerakan islamisasi
pada abad ke-13 berperan penting dalam merubah sejarah Indonesia, sekaligus
menandai awal era modern di negeri ini.116
Walaupun sejarah kedatangan Islam
masih misterius atau dengan kata lain masih diperdebatkan oleh para sarjana, tetapi
kenyataannya Islam berhasil menjadi agama yang dianut oleh masyoritas penduduk
Nusantara. Tidak hanya itu, dengan jumlah penduduk yang besar, Islam di
Indonesia menjadi komunitas Muslim terbesar di dunia dibandingkan dengan
jumlah umat Muslim di tempat dimana Islam pertama kali diperkenalkan oleh Nabi
Muhammad SAW.
Sejarah pembentukan Cirebon tidak dapat dipisahkan dari peran penting Islam
di masa silam. Islam masuk ke daerah Cirebon secara bertahap mulai abad ke-15.
Namun, sebelum berdirinya Kerajaan Islam Cirebon, daerah ini belum merupakan
114
Cortesao, The Summa Oriental…, h. 167. 115
Ekajati, Sejarah Kuningan…, h. 34. 116
M. C. Ricklefs, The History of Modern Indonesia Since c. 1200, vol. 3, (Great
Britain: Palgrave Macmillan, 2001), h. 23.
99
pusat penyebaran agama Islam. Titik tolak Cirebon sebagai pusat penyebaran Islam
khususnya di tatar Sunda adalah sejak berdirinya Kerajaan Islam Cirebon. Jika
Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran Islam di daerah Jawa Timur, maka
Kerajaan Cirebon adalah titik central penyebaran agama Islam di Jawa Barat,
terutama sejak Sunan Gunung Jati menjadi memimpin Cirebon.117
Beberapa literatur menyebutkan bahwa proses islamisasi di Cirebon melalui
jalur yang sama dengan wilayah lainnya di Nusantara, yakni melalui maritim. Islam
pada mulanya datang ke wilayah pesisir Cirebon tepatnya di pelabuhan Muara Jati,
wilayah Pesambangan yang menjadi bagian dari wilayah Singapura. Maka, tidak
heran komunitas Muslim yang pertama kali muncul di daerah pesisir seperti dalam
cerita tiga komunitas Tionghoa Muslim yang berasal dari rombongan Cheng Ho dan
Syekh Nurjati yang mendirikan lembaga pendidikan di bukit Amparan Jati,
Pesambangan. Para pelaku islamisasi pun baik yang berasal dari kalangan pribumi
seperti Haji Purwa maupun di luar wilayah Cirebon datang dengan status sebagai
pedaganag yang banyak bergerak di dunia perdagangan.118
Ada beberapa tokoh yang erat kaitannya dengan proses islamisasi di wilayah
Cirebon dan sekitarnya, selain penduduk pribumi, juga Syekh Nurjati, Syekh
Bayanullah dan Syekh Maulana Maghribi. Kedua pendakwah awal merupakan
kakak beradik, putra Syekh Datuk Ahmad Malaka yang menurut penjelasan sejarah
memiliki ikatan dengan Syekh Hasanuddin. Syekh Nurjati datang ke pelabuhan
Muara Jati lebih lambat, yakni tiga sampai lima tahun setelah kedatangan Syekh
Hasanuddin atau Syekh Quro ke tempat yang sama. Sementara itu, Syekh
Bayanullah datang ke wilayah Cirebon paling akhir dibandingkan dengan para
pendakwah lainnya, dan ia sendiri memusatkan gerakan islamisasinya di wilayah
Kuningan.119
Dalam konteks di atas, Syekh Nurjati lebih memilih untuk datang ke pelabuhan
Muara Jati yang saat itu menjadi entre port ke wilayah Cirebon. Sama seperti apa
yang dilakukan Syekh Hasanudin, Syekh Nurjati membangun pesantren yang
berlokasi dekat dengan pelabuhan, yaitu di Bukit Amparan Jati, Pesambangan.
Lembaga pendidikan Islam inilah yang tercatat sebagai tempat belajar para
penguasa Kerajaan Islam Cirebon seperti Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung
Jati. Syekh Nurjati tidak melakukan expansi dalam menyebarkan dakwah Islam dan
tidak terlibat dalam proses pembentukan Kerajaan Cirebon. Ia tampil sebagai guru
spiritual dan penasehat, serta mengajarkan para calon penguasa Kerajaan Islam
Cirebon. Sementara peran politik lebih menonjol dan terlihat pada Syekh
Abdurrahman (Pangeran Panjunan), Syekh Abdurrahim (Pangeran Kejaksaan), dan
Syarifah Baghdad.120
Tahap awal penyebaran agama Islam berlangsung melalui pesantren dalam
lingkungan terbatas. Di pesantren, santri dididik menjadi kader-kader penyebar
agama Islam. Setelah mereka memiliki atau menguasai ajaran Islam, mereka
117
H. M. Ambary, Peranan Cirebon sebagai pusat perkembangan dan penyebaran
Islam, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), h. 46-47. 118
Adeng, dkk., Kota Dagang Cirebon…, h. 18-19. 119
Ekajati, Sejarah Kuningan…, h. 54. 120
Rosyidin, Kerajaan Cirebon, h. 35.
100
kembali ke daerah masing-masing untuk menyebarkan agama Islam, juga untuk
membantu tokoh-tokoh penyebar agama di daerah tersebut.
Penyebaran dan pengajaran ajaran Islam di Cirebon dilakukan menggunakan
metode dakwah. Sunan Gunung Jati melakukan dakwah Islam dengan berkeliling ke
berbagai penjuruh daerah yakni dari satu tempat ke tempat lain di Jawa Barat,
hingga mencapai daerah Pagedingan (wilayah barat dan selatan Sumedang Larang),
daerah Ukur Cibaliung (sekarang wilayah Bandung), daerah Batulayang, dan daerah
Timbanganten (sekarang daerah Garut).121
Dakwah dengan cara berkeliling pada umumnya berlangsung secara efektif dan
efisien. Hal ini terjadi karena didukung oleh dua faktor, yaitu: pertama, dakwah
dilaksanakan melalui pendekatan sosial budaya dengan pola akomodatif. Dalam
berdakwah, Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengetahuan masyarakat tentang
unsur-unsur legenda dan mitos. Kedua, kesalehan dan sikap keteladanan (uswatun
hasanah) para penyebar agama Islam. Setelah diajarkan tentang ajaran agama
Islam, para mualaf juga diberikan contoh kesalehan sosial dengan memberi teladan
bagaimana ajaran agama Islam itu dilaksanakan atau dipraktekkan.122
Dalam melaksanakan dakwah Islam, para penyebar agama Islam memadukan
ajaran agama Islam dengan tradisi dan unsur-unsur budaya termasuk kesenian
seperti gamelan, wayang, tari topeng, sintren dan lain-lain, yang di kalangan
masyarakat dijadikan obyek dakwah. Misalnya, gamelan dimainkan menjelang
waktu salat Jumat dengan maksud menarik warga masyarakat untuk berkumpul dan
mendengarkan dakwah. Dengan demikian, mereka dapat dengan mudah diajak
untuk melaksanakan salat Jumat. Sama halnya di Demak, gamelan dijadikan media
dakwah Islam sebagaimana di masa pemerintahan Raden Fattah. Selain itu,
pertunjukkan wayang kulit juga digunakan sebagai media dakwah Islam, karena
wayang kulit pada dasarnya adalah mitologi orang Jawa. Sunan Gunung Jati dan
Sunan Kalijaga misalnya, mereka menggunakan kesenian wayang dan tari topeng
sebagai media dakwah Islam. Dalam pertunjukan wayang kulit, penonton hanya
dapat melihat bayang-bayang wayang yang bersifat abstrak. Gambaran abstrak
seperti itu mirip dengan syraiat, ilmu kalam dan ilmu fikih. Dalam dakwah dengan
menggunakan media wayang, masyarakat ditekankan untuk mengambil pelajaran
dari cerita lakon wayang yang berisi sikap dan perilaku, termasuk soal bagaimana
tindakan yang harus diambil ketika menghadapi persoalan hidup dan juga cara
penyelesaiannya.123
Sedari awal Kesultanan Cirebon sudah menjadi basis bagi pengembangan
Islam yang toleran, inklusif, dan moderat. Kesultanan Cirebon menjadikan budaya
sebagai alat untuk dakwah. Ini sangat relevan untuk masyarakat Indonesia yang
majemuk dan kaya budaya dibutuhkan sikap “tengahan” dalam berbudaya dan
beragama. Secara tidak langsung Kesultanan Cirebon telah turut berkontribusi
121
Rosyidin, Kerajaan Cirebon, h. 36. 122
W. Hernawan & Ading Kusdiana Biografi Sunan Gunung Djati: Sang Penata
Agama di Tanah Sunda, (LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). 123
Fahrur Razi, “NU dan Kontinuitas Dakwah Kultural”. Jurnal Komunikasi Islam, vol.
01, no. 02, 2011, h. 161-172.; Anif Arifani, “Model Pengembangan Dakwah Berbasis
Budaya Lokal”, Jurnal Ilmu Dakwah, vol. 4, no. 15, 2010, h. 849-878.
101
dalam peradaban Islam yaitu dengan sikap „tengahan”nya sehingga terbentuk
muslim-muslim yang berpaham keagamaan moderat, akomodatif dan inklusif.
Ada beberapa jalur penyebaran agama Islam ke daerah Jawa Barat dari Cirebon
yaitu pertama: Cirebon, Kuningan, Talaga dan Galuh. Kedua: Cirebon, Kadipaten,
Majalengka, Darmaraja dan Garur. Ketiga: Cirebon, Sumedang, dan Bandung.
Keempat: Cirebon, Talaga, Sagalaherang dan Cianjur. Sementara daerah lain yang
menjadi sasaran penyebaran agama Islam adalah Indramyu dan Tasikmalaya. Jalur
dakwah Islam tersebut menunjukkan bahwa islamisasi di sebagian wilayah Jawa
Barat berasal dari Cirebon. Penduduk yang mendapatkan dakwah Islam menerima
ajaran Islam dengan senang hati karena para penyebar dakwah pandai dan bijaksana
dalam melakukan pendekatan dengan penduduk setempat. Dengan demikian,
penyebaran agama Islam di beberapa daerah sebagaimana disebutkan berlangsung
secara damai.124
Sebelum Islam berkembang di Cirebon, wilayah ini tidak banyak dikenal.
Ketika pengaruh Islam di Cirebon begitu kuat, maka barulah Cirebon mulai dikenali
dan semakin kuat. Beberapa sumber tradisi sebagaimana dalam naskah Babad
Cerbon dan Purwaka Caruban Nagari menyebutkan bahwa Cirebon pada mulanya
merupakan sebuah desa nelayan yang tidak berarti, bernama Dukuh Tegal Alang-
Alang atau Lemah Wungkuk. Dahulu wilayah tersebut bernama Lemah wungkuk
yang dipimpin oleh Ki Gedeng Alang-Alang. Ia merupakan salah satu kuwu yang
diangkat oleh penguasa Pajajaran sebagi kepala pemukiman.125
Kekuasaan Cirebon
saat itu meliputi batas Sungai Cipamali di sebelah timur, Cigugur (Kuningan) di
sebelah selatan, pegunungan sebelah barat dan junti (Indramayu) di sebalah utara.
Penyebaran Islam di wilayah-wilayah luar Pesambangan lebih didominasi oleh
peran Pangeran Cakrabuana dengan membangun wilayah Cirebon Larang dan
Sunan Gunung Jati yang mendirikan Kerajaan Islam Cirebon. Pada mulanya
Pangeran Cakrabuana didukung oleh 52 pengikutnya. Dukungan juga diberikan
oleh Ki Danusela yang nantinya bergelar Ki Gedeng Alang-Alang ketika diangkat
menjadi kuwu pertama Cirebon Larang. Sementara Raden Walangsungsang
bertugas untuk mengurus persoalan sumber daya alam yang ada di wilayah Cirebon
Larang.126
Raden Walangsungsang memiliki beberapa gelar seperti Pangeran Cakrabuana,
Ki Somadullah yang artinya tempat berlindungnya agama Allah dan Haji Abdullah
Iman ketia ia belajar dari Syekh Nurjati dan sudah menunaikan ibadah haji.
Pemberian gelar sudah menjadi sebuah tradisi budaya politik di Nusantara untuk
melegitimasi kekuasaan atas dasar agama. Oleh karena itu, pangeran Cakrabuana
dipandang sebagai penguasa dan pemilik wilayah dan rakyat serta representasi
kekuasaan tuhan dimuka bumi yang akan melindungi ajaran Islam dan kaum
Muslim. Hal ini juga relevan ketika Cirebon digambarkan sebagai pusat alam
semesta (puser bumi). Sementara Sunan Gung Jati sebagai penerus Pangeran
Cakrabuana bergelar “Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep
Panatagama Aulia Allah Kutubizaman Kholifatur Rosullullah Shallollahu Alahi
124
Rosyidin, Kerajaan Cirebon, h. 67. 125
Atja, Carita Purwaka Caruban…, h. 33. 126
Kertawibawa, Pangeran Cakrabuana…, h. 148-149.
102
Wassalam”. Gelar tersebut memiliki banyak makna, baik secara politik ataupun
keagamaan. Gelar itu juga menggambarkan tingginya peran dan status serta
kekuasaan dan kewenangan di Kerajaan Islam Cirebon. Ia tidak hanya berperan
sebagai raja, tetapi juga menjadi referensi ajaran agama Islam bagi masyarakat
Muslim.127
Gerakan Islamisasi secara masif baru dilakukan pada masa kepemimpinan
Sunan Gunung Jati, yang statusnya juga sebagai salah satu anggota Wali Songo. Di
awal penulis telah menjelaskan bahwa bahwa tugas utamanya Sunan Gunung Jati
adalah mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam seluas-luasnya. Hanya saja,
peran Sunan Gunung Jati berbeda denga para wali lainnya, Sunan Gunung Jati
mempunyai kekuasaan penuh dengan status sebagai raja. Maka itu, gerakan dakwah
Islam tidak hanya dilakukan sebagaimana Sunan Bonang dan Sunan Giri yang
mendirikan pusat pendidikan Islam, tetapi juga menggunakan bala tentara Kerajaan
Islam Cirebon. Hal inilah yang mungkin membenarkan pendapat Ricklefs yang
mengatakan meskipun secara umum dakwah Islam di Nusantara dilakukan secara
damai, tetapi bukan berarti tidak ada yang menggunakan pedang atau dengan cara
perang.128
Hal ini dapat dilihat saat Sunan Gunung Jati mengislamkan Luragung, ia
menggerakan pasukan untuk menaklukan Kerajaan Hindu Luragung.129
Begitupun,
ketika ia mengirim anaknya Maulana Hasanudin (Pangeran Sabakinkin) untuk
mengislamkan masyarakat yang ada di wilayah Banten dan Sumatera bagian
selatan.
Dengan demikian, di masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, Cirebon menjadi
salah satu basis syiar dan kejayaan Islam. Pada masa itu, terjadi beberapa
penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah seperti Indrmayu, Karawang, Bekasi,
Tanggerang dan Serang Banten, termasuk takluknya beberapa kerajaan seperti
Kerajaan Galuh (1528) dan Kerajaan Talaga (1530). Selain itu, bukti kejayaan
Cirebon dapat dilihat pada bangunan fisik seperti Keraton Pakungwati (Keraton
Kasepuhan), Pelabuhan Muara Jati, Mesjid Agung Sang Ciptarasa dan sebagainya.
Sejak Syarif Hidayatullah tinggal di Keraton Pakungwati, tempat ini menjadi
awal mula dari semua kegiatan perkembangan Islam secara luas dan masif. Dalam
sistem pemerintahan diterapkan nilai-nilai Islam untuk mengelola Kerajaan Islam
Cirebon. Sebagai seorang pimpinan politik dan agama, struktur kenegaraan yang
didasarkan pada paham kekuasaan religius. Sang pemimpin bukan hanya sebagai
manusia biasa, namun memiliki kekuatan supranatural. Raja menjadi medium untuk
menghubungkan manusia dengan alam gaib. Dengan demikian, misi pemerintahan
Sunan Gunung Jati merupakan perpaduan antara sistem pengelolaan negara dengan
dakwah agama Islam sehingga aspek-aspek yang ada di pemerintahan, pengendalian
masyarakat dan pengembangan agama menjadi satu yang tidak dapat terpisahkan.
127
Z. Masduqi, dkk., Islamisasi, Suksesi Kepemimpinan, dan Awal Munculnya
Kerajaan Islam Cirebon: Kajian dan Penulisan Sejarah Kesultanan Cirebon, (Jakarta:
Puslitbang Lektur & Khazanah Keagamaan Balitbang Diklat Kementrian Agama RI, 2012),
h. 126. 128
Ricklefs, The History…, h. 17. 129
Adeng, dkk., Kota Dagang Cirebon…, h. 29.
103
Pada tahun 1483, Keraton Pakungwati yang dahulu dibangun oleh pangeran
Cakrabuana diperluas dan ditambah dengan bangunan-bangunan pelengkap, dan
dikelilingi tembok setinggi 2,5 meter dengan ketebalan 80 cm pada areal tanah
seluas 20 hektar. Sementara, untuk menjaga keamanan keraton, dibangun tembok
setinggi 2 meter mengelilingi Ibu kota seluas 50 hektar. Tembok keliling keraton
dilengkapi dengan pintu gerbang.130
Selain itu, upacara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Keraton
Cirebon mulai diadakan dan dilaksanakan dengan meriah dan secara besar-besaran
ketika Sunan Gung Jati diangkat sebagai Wali Kutub pada tahun 1470 M. Perayaan
keagamaan tersebut oleh masyarakat Cirebon dikenal dengan nama Panjang
Jimat,131
sekaligus menandai bahwa Sunan Gunung Jati dan keturunannya
menempati struktur sosial yang tinggi dan sebagai penata agama.132
Di samping itu,
salah satu tempat yang menjadi pusat kegiatan agama Islam di Kesultanan Cirebon
adalah Mesjid Agung Sang Ciptarasa. Sunan Gung Jati menjadi raja di Kesultanan
Cirebon sekaligus sebagai anggota Wali Songo. Dengan demikian, segala
aktivitasnya tidak terlepas dari upaya untuk mendakwahkan ajaran agama Islam. Itu
sebabnya, pada 1480 Sunan Gunung Jati mendirikan Mesjid Agung Sang Cipta
Rasa yang terletak di samping kiri keraton dan di sebelah barat alun-alun. Dalam
pembangunan Mesjid Agung Sang Cipta Rasa, Sunan Gunung jati dibantu oleh
Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Sementara yang menjadi arsitek dalam
pembangunan mesjid tersebut adalah Raden Sepat (arsitek Kerajaan Majapahit).133
Adapun dengan informasi mengenai pendirian Mesjid Agung Sang Cipta Rasa
dapat ditelusuri dalam Naskah Kuningan, dijelaskan bahwa:
“...Sejarah tanah Sunda menjadi mukmin semua lalu dibangun mushola,
Mesjid Agung di Carbon. Para wali diundang, dan kesembilannya sudah hadir
yaitu, Sunan Bonang, Pangeran Majagung, Sunan Jati sebagai tuan rumah,
Sunan Kalijaga, Syekh Bentong, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Lemah
Abang, Sunan Giri, dan Sunan Kudus. Semua sepakat untuk melaksanakan
pembangunan Mesjid Agung di Carbon. Tiga buah amal sudah diselesaikan,
yakni pertama membangun negara yaitu negaranya orang shaleh, kedua
membangun sabilullah, yaitu memerangi orang kufur dan menjadikannya
beragama Islam dengan seizin Allah, dan ketiga membnagun mesjid tempat
utuk orang shalat dan seterusnya...”.134
Selain yang dijelaskan dalam naskah di atas, informasi terkait Mesjid Agung
Sang Cipta Rasa juga dapat ditelusuri dalam sumber yang menjelaskan bahwa
Mesjid Agung Sang Cipta Rasa yang juga Mesjid Agung Pakungwati adalah
130
H. Erwantoro, Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon, (Bandung: Balai Pelestarian
Sejarah dan Nilai Tradisional, 2012), h. 175. 131
Lubis, Sejarah Kota-kota, h. 184-185. 132
S. Siddique, “Relics of the Past: A Sociological Study of the Sultanates of Cirebon,
West Java”, (Ph.D. Dissertation, Bielefeld, 1977), h. 91. 133
Lubis, Sejarah Kota-kota, h. 45. 134
A. N. Wahyu, Sajarah Wali Syeikh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati: Naskah
Kuningan, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2007).
104
sebagai masjid Kerajaan Cirebon. Misalnya dalam Naskah Mertasinga, dijelaskan
bahwa:
“...setelah penobatan ini Sinuhun Sunan Gunung Jati berkehendak untuk
membangun Mesjid Agung Pakungwati yang kelak akan menjadi pusaka di
Carbon. Uwaknya diminta untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk
membangun mesjid itu. Dari seluruh pelosok negeri telah dikumpulkan kayu
yang baik untuk dipakai sebagai tiang. Sunan Rangga sudah mengerti akan
keinginan putranya itu. Dengan segera sudah terkumpul banyak kayu-kayu
yang diperlukan. Tukangnya berjumlah seratus orang, sebanyak bahan yang
ada, atap sirap sudah dipilih, paku dan batu bata sudah terkumpul di
Pakungwati. Kemudian Sinuhun Jati berkata kepada Syekh Datuk Kahfi:
“Kakanda Datuk Khapi tolong tuliskan surat untuk dikirimkan ke negara Bani
Israil, sampaikan kepada Adinda Nurullah agar mengupayakan kayu jati.
Mintalah utamanya, yang panjang untuk dijadikannya sakagurunya hanya
empat buah saja yang dibutuhkan, satu tiang satu saka dari Mesir sebagai
sumbangannya Babu Dampul. Satu dari Bani Israil sebagai sumbangannya
Adinda Nurullah, dan satu lagi dari Surandil sumbangannya dari Syekh
Bentong. Segera Datuk Kahfi menulis surat tersebut dan mengirimkannya,
sementara itu, yang membangun terus bekerja, sambil menunggu datangnya
kiriman ke empat kayu sakaguru dari negara Arab...”.135
“... setibanya Sinuhun Jati di Dalem Agung, beliau berkehendak untuk segera
mendirikan mesjid yang patakannya sudah didirikan. Semua wali sangat
bersemangat dalam membantu pembnagunan mesjid ini. Mereka telah
mendirikan rangkanya bersama-sama. Ketika keesokan harinya terjadi
perselisihan lagi mengenai arah kiblat. Sebagian mengatakan kurang ke
selatan, lainnya mengatakan kurang ke utara, dan lainnya mengatakan sudah
tepat arah kiblat. Sehingga kerangka mesjid itu diangkat berpindah-pindah
berubah arah setiap kali terdengar pendapat baru. Demikian berlangsung tak
habis-habisnya. Sunan Kalijaga memberikan penyelesainnya seperti yang
dilakukannya waktu di Demak. Setelah selesai pembangunan Mesjid Agung
Carbon semua wali memanjatkan puji syukur dan para wali melakukan shalat
subuh. Waktu itu usia Sinuhun Jati 113 tahun, kemudian para wali
memberikan sumbangannya untuk mesjid ini. Sunan Bonang menyumbangkan
satu tikar yang digelarkan di utara, Syekh Bentong menyumbang satu tikar
yang berasal dari Madinah dan digelar di paimaman dan di sebelah utara,
Sunan Jati menyumbang satu tikar yang berasal dari Pulau Majeti dan
dipasang di tengah paimaman. Sunan Kalijaga menyumbang satu tikar yang
digelar di sebelah utara tikar Sunan Purba. Pada waktu itu, semua wali
bergantian menjadi imam shalat Jum‟at di Mesjid Agung. Pangeran Makhdum
yang menjadi juru qomat shalat Jum‟at. Pangeran Datuk Kahpi yang
memegang waman ah sanun-nya (yang mengatur mesjid dalam hal jadwal,
shaf shalat), Tuan Jopak dan Tuan Bumi yang melayani, Sunan Panggung,
135
A. N. Wahyu, Sajarah Wali Syeikh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati: Naskah
Mertasinga, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2005), h. 68-99.
105
Pangeran Kajoran, bersama Pangeran Drajat tanggung jawab memeganag
hukum-hukum, semuanya diatur dengan persetujuan para wali.136
Mesjid Agung Sang Cipta Rasa menjadi salah satu pusat kegiatan keagaman di
wilayah Kesultanan Cirebon. Pembangunan mesjid ini merupakan bagian tidak
terpisahkan dari pusat pemerintahan Kesultanan Islam masa lalu. Keraton, mesjid,
alun-alun dan pasar merupakan kesatuan yang membentuk ini kota kuno Kerajaan
Islam. Mesjid Agung Sang Cipta Rasa memperlihatkan gaya bangunan tradisional
yakni memiliki pintu masuk berbentuk Gapura Bentar, dan denahnya dua tumpang
berjumlah ganjil.
C. Masuknya Etnis Tionghoa ke Cirebon
Dalam pembentukan komunitas Muslim di Nusantara, Reid sebagaimana
dikutip Hidayat berpendapat bahwa adanya hibridisasi di mana pada awalanya
label-label etnik seperti Jawa-Melayu yang merupakan keturunan hasil perkawinan
campur antara lelaki etnis Tionghoa dengan perempuan lokal yang sudah
berlangsung berabad-abad. Telah disebutkan bahwa sejak awal penduduk Cirebon
terdiri dari campuran beberapa etnis. Berbagai literatur menyebutkan bahwa
sebelum berdirinya Kerajaan Islam di Cirebon, orang-orang Arab dan Tionghoa
sudah ada dan menetap di daerah ini. Diduga kuat beberapa saudagar Arab menetap
di pesisir Cirebon sejalan dengan Cirebon menjadi kota pelabuhan, dan bersamaan
dengan masuknya agama Islam. Mengenai kedatangan etnis Tionghoa ke Cirebon,
pengamat sejarah Jeremy Wijaya mengatakan etnis Tionghoa pertama kali masuk
ke Cirebon diperkirakan sejak abad ke-8 yang ditandai dengan pendirian Klenteng
Kak Tiao Kak Sie dekat pelabuhan Cirebon sekarang.137
Dengan berdirinya
klenteng tersebut, penulis berspekulasi bahwa sebagian besar etnis Tionghoa yang
menetap di Cirebon menganut agama leluhurnya, Konghucu.
Ketika Cirebon berubah status menjadi Kerajaan Islam, masyarakat Cirebon
secara garis besar terdiri dari tiga golongan sosial. Pertama, golongan bagsawan
tingkat atasraja atau sultan beserta keluarganya, serta para pejabat tinggi
kerajaanelit birokrasi dan agama. Kedua, golongan bangsawan tingkat
menengahpegawai kerajaan tingkat menengahkesatria, demang, tokoh agama,
saudagarTionghoa dan Arab. Ketiga, rakyat biasa (wong cilik)terdiri dari
kelaurga petani, nelayan dan pedagang kecil.
Ada juga pendapat yang mengatakan kedatangan etnis Tionghoa ke Cirebon
terjadi pada awal abad ke-15, ditandai dengan berdirinya kampung pecinan yang
dibangun tahun 1415 oleh anak buah Cheng Ho sewaktu singgah di pelabuhan
Muara Jati. Berbagai literatur mengatakan bahwa etnis Tionghoa yang dibawa
Cheng Ho ke Pulau Jawa menetap di Banten, Cirebon, Semarang, Juwana, Jepara,
Gresik, Surabaya, dan Bangil. Sementara kehidupan sehari-hari dari etnis Tionghoa
dan Arab yang menetap di Cirebon bercampur dengan penduduk pribumi, bahkan
terjadi perkawinan silanglaki-laki Tionghoa dan Arab menikah dengan
perempuan pribumi. Kedua etnis asing tersebut masing-masing tinggal secara
136
Wahyu, Sejarah Wali…, h. 68-99. 137
S. M. Hidayat, Masyarakat dan Kebudayaan Cina di Indonesia, (Bandung: Tarsito,
1977).
106
berkelompokdisebut pecinan (kampung Cina) dan kampung Arab. Dengan
demikian, terjadi sebuah akulturasi budaya, termasuk bahasa.138
Eksistensi etnis Tionghoa di Nusantara sebenarnya sudah ada sejak zaman
purba. Hal itu didasarkan pada hasil temuan benda-benda kuno seperti tembikar
kuno di Jawa, Lampung dan Bantanghari serta Kalimantan yang disimpan di
keraton. Selain itu, ditemukan kapak batu yang sedikit dipoles dari zaman
neolitikum yang mempunyai persamaan dengan kapak batu giok atau zamrud yang
ditemukan di Tiongkok, dan berasal dari zaman yang sama.139
Namun di Nusantara,
kedatangan etnis Tionghoa lebih dikenal pada abad ke-15 tepatnya di masa Dinasti
Ming sedang berkuasa. Etnis Tionghoa dari Yunan mulai berdatangan untuk
menyebarkan agama Islam terutama di Pulau Jawa. Dengan dipimpin Cheng Ho,
armada dan etnis Tionghoa berdatangan ke Nusantara dan mendarat di pantai
Simongan Semarang.140
Pelayaran Cheng Ho di Nusantara mempunyai beberapa latar belakang.
Pertama, Cheng Ho didukung oleh Dinasti Ming yang mempunyai kekuatan amat
kuat. Usaha pertanian serta produk-produk bermutu dan maju seperti kain sutra,
porselen, alat besi, dan sebagainya dimiliki oleh mereka. Dalam konteks ini Cheng
Ho mendapatkan bantuan material yang cukup dan baik dari Dinasti Ming. Kedua,
sejak lama sudah terjalin hubungan erat antara etnis Tionghoa dengan negara-
negara Asia-Afrika. Dengan hubungan yang baik itu membuat perniagaan antara
Tionghoa dengan negara-negara Asia semakin banyak, utamanya antara pemerintah
dan pedagang. Hal ini membuat terbukanya lapangan pekerjaan sebagai awak kapal
yang sudah berpengalaman, terlatih dan handal. Ketiga, teknologi mereka dalam
membuat kapal sudah semakin maju. Kapal terdiri dari 50-60 kabin dan mampu
membawa lebih dari 1.000 penumpang dalam pelayaran jauh. Jangkar perahu begitu
besar dan memerlukan 200-300 orang jika hendak mengangkatnya. Badan kapal
merupakan sususnan ruang-ruang yang terpisah satu sama lainnya. Meskipun
terbentur kencang dan sebagainya, kapal tidak akan mudah tenggelam bila hanya
sebagian saja yang rusak.141
Pengiriman armada yang dipimpin Cheng Ho bertujuan untuk mengamankan
jalur pelayaran niaga di Asia Tenggara.142
Mengingat lokasi ini banyak diganggu
oleh bajak laut. Selain itu, Dinasti Ming ingin mempromosikan kejayaan dinastinya,
serta mengembangkan pengaruh politik dan militernya kepada negara-negara Asia.
Ketika memimpin pelayaran, Cheng Ho membawa pasukan yang banyak, tiap
armada terdiri dari 62 buah kapal yang disebut bao chuan (kapal harta). Kapal besar
yang dibawanya berukuran: panjang 132 meter dan lebar 54 meter. Kapal ini
138
H. J. de Graaf, dkk., Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI antara Historisitas dan
Mitos, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1998). 139
B. G. Setiono, Tionghoa dalam Pusaran Politik, (Jakarta: Transmedia Pustaka,
2008), h. 25. 140
A. Budiman, Masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia (The Chinese Muslim
Community in Indonesia), (Semarang: Tanjung Sari, 1979), h. 57. 141
K. Yuanzi, Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah Cheng Ho,
(Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2007), h. 12. 142
Hidayat, Masyarakat dan Kebudayaan…, h. 76.
107
mampu membawa 27.800 pasukan dan sejumlah barang-barang, di antaranya emas,
porselen, tembikar, karya seni yang indah, dan kain sutra. Barang barang ini
kemudian ditukarkan dengan gading gajah, cula badak, kulit penyu, obat-obatan,
rempah-rempah, mutiara dan batu-batu permata.
Selain kapal penumpang, pasukan armada ini membawa beberapa kapal di
antaranya: kapal tangki air, kapal pengangkut kuda untuk pasukan kavaleri, kapal
tempur, dan kapal patroli cepat yang punya banyak dayung. Kapal-kapal yang
dibawa Cheng Ho menimbulkan rasa hormat bercampur kagum, takjum dan takut.
Armada-armada ini dipandang sebagai pasukan yang gagah dan unik. Ketika
armada kembali ke Tiongkok mereka membawa pulang berbagai macam hadiah dan
upeti dari negara-negara yang dikunjunginya.
Kedatangan etnis Tionghoa di Nusantara selain adanya pelayaran dari Cheng
Ho, juga disebabkan karena bencana alam dan peperangan yang tidak ada henti-
hentinya membuat etnis Tionghoa secara nekat meninggalkan negeri mereka dan
mencoba nasib baru di negeri orang dengan hanya berbekal buntalan pakaian.
Ribuan etnis Tionghoa menyebar ke berbagai penjuru dunia, utamanya di Asia
Tenggara. Kondisi tersebut menandakan bagian penting migrasi Tionghoa secara
besar-besaran ke seluruh dunia, dan mencapai puncaknya pada abad ke-15.143
Kontak sosial antara etnis Tionghoa dan masyarakat Cirebon menurut penulis
terjadi dalam tiga gelombang, yaitu dimulai sejak abad 15, yang ditandai dengan
kedatangan Cheng Ho dan para pasukannya. Dalam perjalanannya, rombongan etnis
Tionghoa melakukan persinggahan ke beberapa pelabuhan yang ada di sepanjang
pesisir pantai utara Pulau Jawa, termasuk pelabuhan Muara Jati, Pesambangan yang
pada saat itu menjadi salah satu bagian wilayah Singapura. Dalam rombongan
tersebut, turut serta beberapa tokoh seperti Haji Kung Wu Ping, Ma Huan144
dan
Feh Sin. Bahkan Cheng Ho dan pasukannya mendirikan Mercusuar.145
Namun
menurut Permadi sebelum kedatangan Cheng Ho dan pasukannya, para utusannya
(Tilik Sandi) sudah datang terlebih dahulu ke Cirebon. Para utusan inilah yang
memberi kabar tentang kondisi Cirebon yang memiliki air bersih dari gunung
Ciremai dan kayu jati. Permadi juga mengatakan bahwa Mercusuar itu sudah
dibangun oleh para utusan Cheng Ho sebelum Cheng Ho datang ke Cirebon. Jadi,
Cheng Ho datang ke Cirebon memang sudah direncanakan.146
Mengenai kedatangan rombongan Cheng Ho ke pelabuhan Muara Jati, Tim
Peneliti Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merujuk
kepada pandangan Mills bahwa kunjungan terjadi pada tahun 1415. Kunjungan ini
merupakan rangkaian perjalanan pulang dari kunjungan ke Surabaya menuju
143
Graaf, Cina Muslim…, h. 56. 144
Menurut Purwaka Caruban Nagari, Ma Huang adalah sekretaris Cheng Ho. Ia
datang ke Cirebon bersama rombongan Tionghoa. Di Cirebon ia dikenal dengan nama
Muhammad Hasan. Setelah tingal di Cirebon Ma Huang dinikahkan kepada saudara Ki
Gedeng Tapa atau Ki Gedeng jumajan Jati yang bernama Nyai Rara Rudra. Setelah menikah
ia bergelar Ki Dampu Awang. Lihat B. B. Kertawibawa, Pangeran Cakrabuana Sang
Perintis Kerajaan Cirebon, vol. 1 (Bandung: PT. Kiblat Buku Utama, 2007). 145
Atja, Carita Purwaka Caruban…, h. 31. 146
Wawancara dengan Permadi (Tokoh Mayarakat Tionghoa) pada tanggal 26
September 2019
108
Palembang dan sempat singgah di beberapa pelabuhan di Pulau Jawa, salah satunya
Cirebon. Ketika rombongan Muhibah Cheng Ho datang ke Palabuhan Muara Jati,
para rombongan disambut oleh penguasa lokal saat itu, yaitu Ki Gedeg Jumajan
Jati.
Pada perkembangan selanjutnya, Haji Kung Wu Ping yang merupakan anak
buah Cheng Ho membentuk komunitas Tionghoa muslim Hanafi di tiga tempat
yaitu di Sarindil, Sembung dan Talang. Masing-masing komunitas itu kemudian
diberi tugas. Komunitas pertama ditugaskan untuk mencari kayu jati dan
menghasilkan kayu jati untuk memperbaiki kapal, sedangkan komunitas kedua
ditugaskan untuk memelihara mercusuar yang sudah dibangun. Sementara
komunitas ketiga ditugaskan menjaga dan merawat pelabuhan. Dengan menetapnya
kaum Tionghoa Muslim merupakan salah satu cikal bakal lahirnya komunitas
Muslim di Cirebon, hingga pada akhirnya mereka mendirikan mesjid sebagai
tempat ibadah.147
Namun, dari beberapa wilayah yang ditempati oleh ketiga komunitas Tionghoa
sebagaimana di atas, hanya ada satu tempat yang berkembang Islamnya dan masih
memegang teguh keimanannya yakni di Sembung. Adapun komunitas Tionghoa
Muslim di Sarindil dan Talang banyak yang murtad. Mereka yang tinggal di dua
wilayah seperti Sarindil dan Nagari Japura menjadi sepi, bahkan menjadi sebuah
tempat untuk pertapaan. Sementara Talang di Singapura yang didominasi etnis
Tionghoa pemeluk Konghucumerubah mesjid yang ada di sana menjadi
Klenteng.148
Menurut penulis kemunduran itu bisa jadi karena berhentinya
muhibbah Laksamana Cheng Ho ke Jawa. Kemudian Haji Tan Eng Hoat (Maulana
Ifdhil Hanafi/Pangeran Adipati Wirasanjaya) mengembangkan pemukiman
Tionghoa Muslim. Haji Tan Eng Hoat inilah yang kemudian membantu Sunan
Gunug Jati menyebarkan dan mengembangkan Islam ke Priangan timur sampai ke
Garut, juga ikut membantu Sunan Gunung Jati melawan Kerajaan Galuh.
Ponakannya yang bernama Tan Sam Cai alias Muhammad Syafei alias
Tumenggung Aria Dwipa Cula juga punya peran penting dalam Kesultanan
Cirebon. Tan Sam Cai pernah menjabat sebagai bendahara kesultanan, bahkan ia
juga merupakan arsitektur Guha Sunyaragi. Selain sebagai administrator yang baik.
Tan Sam Cai berjasa dalam memperkuat Kesultanan Cirebon dengan
keuangannya.149
Ia dipercaya oleh Sunan Gunung Jati menjadi bendahara yang
cakap dan terpercaya pada masa Panembahan Ratu.150
Tan Sam Cai tidak banyak disebut dalam catatan tertulis sejarah kepurbakalaan
Cirebon, akan tetapi perannya secara lisan cukup dikenal di kalangan masyarakat
khususnya etnis Tionghoa yang meyakini bahwa Tan Sam Cai berperan dalam
Kesultanan Cirebon, tepatnya di masa Sunan Gunung Jati memimpin, bahkan ia
sering dikaitkan dengan pembangunan Guha Sunyaragi, selain sebagai salah satu
bendara ulung Kesultanan Cirebon. Meski demikian, asal usul Tam Sam Cai masih
147
Graaf, Cina Muslim…, h. 34-35. 148
Graaf, Cina Muslim…, h. 36. 149
Graaf, Cina Muslim…, h. 42-44. 150
Rusyanti, “Peranan Tan Sam Cai Kong dalam Sejarah Cirebon”. Purbawidya, vol. 2,
no. 1, 2013, h. 105-117.
109
belum jelas sebagaimana De Graaf dalam bukunya mengungkapkan bahwa Tan
Sam Cai merupakan sepupu Tan Eng Hoat (Maulana Ifdil Hanafi/Adipatai Wirya
Sanjaya).151
Pada saat ia menjadi Menteri Keuangan Cirebon pada tahun 1569-1585, Tam
Sam Cai membuka beberapa potensi ekonomi seperti membuka pasar tradisional,
melakukan pencetakan mata uang yang berupa emas dan perak baik itu dinar atau
dirham. Pada masanya, Cirebon pernah mempunyai percetakan uang receh yang
berupa koin mirip Tiongkok kuno. Menurut Iwan Satibi, ketika wafat, Tan Sam Cai
sudah keluar dari Islam, sehingga jasadnya di tolak untuk dimakamkan di komplek
makan Astana Gunung Jati, namun karena jasa dan kemampuanya sebagai salah
satu Menteri Keuangan pada masa Kesultanan Islam, dan lain sebagainya, ia diberi
keistemewaan dengan diberikan tanah khusus untuk dijadikan tempat
pemakamannya, di daerah Sukalila Utara sekarang.152
Tan Sam Cai diduga kuat
berperan penting dalam pembangunan Guha Sunyaragi atau Taman Air Sunyaragi.
Salmon berpendapat bahwa pembangunan Gua Sunyaragi adalah salah satu hasil
menggeliatnya orang-orang Tionghoa di Cirebon. Walaupun tidak secara langsung
meyebut asiteknya adalah orang Tionghoa. Namun, ia menyebut pengaruh orang-
orang Tionghoa. Menurut tradisi lokal bahwa sebelah barat guha di bagian sisi
terlihat menyerupai muka barongsai dan adanya replika makam Putri Ong Tien
yang kemudian menjadi alasan bahwa arsiteknya adalah Tan Sam Cai.153
Selain itu,
bukti eksistensi etnis Tionghoa di Cirebon adalah dengan didirikannya Mesjid
Talang. Mesjid ini menurut Neor, pada awalnya ketika orang Tionghoa sampai di
Cirebon, mereka mendirikan sebuah mesjid yang dinamakan Mesjid Talang untuk
tempat beribadahnya Tionghoa Muslim pada masa kedatanagan Laksamana Cheng
Ho. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, mesjid ini beralih fungsi menjadi
Klenteng.154
Gelombang kedua terjadi pada akhir abad 15 yang ditandai dengan kedatangan
puteri Tiongkok yang bernama Ong Tien Nio bersama para pengawalnya dan
seluruh barang bawaannya.155
Rombongan orang-orang Tionghoa tersebut sampai di
Muara Jati dan bertemu dengan orang-orang keling. Menurut mereka, Sunan
Gunung Jati sedang berdakwah di daerah sekitar Gunung Ciremai yaitu Luragung.
Akhirnya, rombongan tersebut menyusul ke tempat dakwah Sunan Gunung Jati.
Maka bertemulah rombongan Tionghoa dengan Syekh Syarif, Pangeran Cakrabuana
beserta para muridnya. Patih Tionghoa kemudian mengutarakan maksudanya untuk
151
Tan Eng Hoat menjadi Raja Muda bawahan Kesultanan Cirebon dan berkedudukan
di Kadipaten serta menyebarkan mazhab Syafii. Ia meninggal ketika sedang merebut Galuh
dan dimakamkan di sekitar Garut dan Ciamis. 152
Penolakan pemakaman Tan Sai Cai dilakukan oleh Haji Kung Sem Pak di Gunung
Sembung dan berdasarkan permintaan istrinya yaitu Nurleila binti Abdullah Nazir Loa Sek
Cong, akhirnya Tan Sai Cai dimakamkan di sekitar rumahnya. Lihat de Graaf, Cina
Muslim…, h. 40-45. 153
Mengenai pengaruh orang-orang Cina dalam pembangunan jasa tekhnik bangunan.
Lihat Hardjasaputra, Cirebon dalam Lima…, h. 23.; dan N. M. Noer, Menusa Cirebon,
(Cirebon: Dinas Pemuda dan Pariwisata Kota Cirebon, 2009), h. 298. 154
Noer, Menusa Cirebon, h. 300. 155
Atja, Carita Purwaka Caruban…, h. 40-41.
110
mengobati Putri Ong Tien dan siap berbakti untuk Syekh Syarif. Kemudian ia
menyampaikan lamarannya, dan sebagai bentuk lamarannya, ia menyerahkan 150
pengikut Puteri Ong Tin kepada Sunan Gunung Jati.156
Dengan persetujuan
Pangeran Cakrabuana, serta beberapa pertimbangan seperti penyebaran Islam,
dakwah dan mempererat hubungan antar negara, maka lamaran Putri Ong Tien
diterima oleh Sunan Gung Jati. Pernikahan mereka pun dilangsungkan pada 1481
M, akan tetapi dari pernikahan ini tidak dikarunai keturunan. Pernikahan antara
Sunan Gung Jati dan Putri Ong Tin membawa dampak sosial budaya di Cirebon.
Banyak pengaruh budaya Tionghoa yang akhirnya menjadi local wisdom.157
Datangnya orang-orang Tionghoa ke Cirebon adalah sekitar abad ke-18,
mereka datang sebagai orang-orang pelarian dari Batavia. Kemudian terjadi
kerusuhan antara etnis Tionghoa dengan pemerintah Hindia Belanda, yaitu ketika
VOC mengalami defisit keuangan yang berakibat kesejahteraan pegawai kolonial
Belanda terganggu. VOC kemudian mengeluarkan peraturan kepada etnis Tionghoa
agar membayar sebanyak dua ringgit sebagai tanda atau surat izin dalam berdagang.
Maka terjadilah kerusuhan yang puncaknya pada 19 Oktober 1740 M.158
Peristiwa
itu dikenal dengan Geger Pecinan atau Chinezemoord atau peristiwa Angke.
Kejadian ini terjadi ketika para pribumi bersama VOC melakukan pembantaian
terhadap orang-orang Tionghoa. Mereka menjarah rumah, gudang logistik, dan
menjarah aset-aset yang dimiliki di Batavia. Diperkirakan bahwa 10.000 manusia
menjadi korban dalam tragedi ini. Setelah terjadi tragedi Chinezemoord, orang-
orang Tionghoa memutuskan untuk menjauhi politik dan hanya berkonsentrasi
untuk kegiatan ekonomi. Bahkan mereka menerima dengan sabar kebijakan-
kebijakan yang dibebankan kepada mereka yang salah satunya dengan mengisolasi
mereka ke dalam perkampungan khusus yang disebut dengan pecinan. Kebijakan ini
diambil sebagai upaya untuk membendung kemungkinan bersatunya orang-orang
Tionghoa dengan pribumi untuk melawan kolonial Belanda.159
Pada masa pemerintahan Belanda, orang-orang Tionghoa Muslim mengalami
kesulitan berkembang karena adanya tekanan dari pihak kolonial. Bahkan, orang-
orang Tionghoa Muslim berpindah agama mengikuti orang-orang kolonial yang
beragama Kristen. Hal ini disebabkan adanya sebuah sikap permusuhan kepada
orang-orang Tionghoa yang menciptakan ketegangan sehingga keamanan menjadi
sebuah yang berharga. Dengan memeluk agama yang sama dengan penguasa
kolonial. Orang-orang Tionghoa beranggapan akan selamat dan mendapatkan
perlindungan serta rasa aman.160
156
D. K. Laksmiwati, Putri Ong Tien Mengarungi Samudra Asmara Meraih Cinta
Sejati Susuhunan Jati Romantika Caruban Nagarai, cet 2, (Yogyakarta: Deepublish, 2014),
h. 12. 157
A. Afif, Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri,
(Depok: Penerbit Kepik, 2012), h. 7. 158
Priyanto Wibowo, “The 1740 Racial Tragedy and loss off Batavia Sugarcane
Industries”. Paramita, vol. 23, no. 2, 2013, h. 127-136. 159
Afif, Identitas Tionghoa Muslim…, h. 53. 160
L. Suryadinata, Pemikiran Politik Etnis Tionghoa 1900-2002, (Jakarta: PT. Grafiti
Press, 2005), h. 89.
111
Pada abad ke 18, orang-orang Tionghoa berupaya untuk memulihkan citra
positif mereka sebagai salah satu rekan kerja strategis yang dapat menjaga
kestabilan aktivitas perdagangan. Akan tetapi, pemerintah kolonial memanfaatkan
situasi itu dengan memperalat orang-orang Tionghoa sebagai sumber pendapatan
untuk membiayai pekerjaan kolonial seperti pembuatan jalan, rumah gadai dan
beberapa pembangunan lainnya. Di samping itu, orang Tionghoa menyambut
kesempatan itu untuk memperkaya mereka dan menjalankan roda perekonomian
serta menjaga hubungan baik dan berusaha memeprtahankan hubungan dengan
pihak kolonial.161
Dengan datangnya orang Tionghoa ke Cirebon, mereka melakukan pembauran
dengan masyarakat sekitar. Pembauran orang-orang Tionghoa membuat terjadinya
akulturasi dan asimilasi di masyarakat. Mereka membawa tradisi, tata kehidupan,
serta norma-norma yang berlaku. Mereka tetap teguh dan mempunyai sikap
fanatisme terhadap kepercayaan leluhur. Tionghoa Muslim melakukan aktivitas
ritual keagamaan dan tardisi adatnya masih dipegang kuat. Hal ini merupakan bukti
bahwa mereka masih melakukan penghormatan kepada leluhurnya sekaligus
sebagai momen untuk menjaga keharmonisan sesama keluarga walaupun berbeda
keyakinan. Aktivitas budaya orang Tionghoa dapat dilihat dari Barongsai, perayaan
Imlek dan Cheng Beng, ataupun seperti Tionghoa Muslim yang memperingati
perayaan Idul Adha dan Idul Fitri.
Walaupun sebagai warga pendatang, etnis Tionghoa mempunyai keahlian di
bidang ekonomi dari pada orang-orang pribumi. Mereka kebanyakan mempunyai
sifat ulet, rajin, hemat dan dapat dipercaya ketika berdagang. Mereka sebagian
berprofesi sebagai pedagang di berbagai pusat perdagangan. Meskipun sudah
memeluk Islam, kepercayaan Tri Dharma yang sudah melekat dan sejalan dengan
nilai-nilai Islam tetap dilestarikan yaitu sifat dapat dipercaya sehingga mereka dapat
dipercaya dalam bidang perdagangan.162
161
P. Wibowo, “Tionghoa dalam Keberagaman Indonesia: Sebuah Perspektif Historis
tentang Posisi dan Identitas”. In Proceeding of The 4th International Conference on
Indonesian Studies: “Unity, Diversity, and Future”, vol. 13, 2012. 162
P. S. Sopiah, “Inpres No 14 Tahun 1967 dan Implikasinya Terhadap Identitas
Muslim Tionghoa Cirebon”. Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, vol.
5, no. 2, 2017, h. 152-173.
113
BAB IV
RELASI SOSIAL-BUDAYA
ETNIS TIONGHOA DAN MASYARAKAT CIREBON
Pembahasan tentang relasi sosial-budaya etnis Tionghoa dan masyarakat
Cirebon erat kaitannya dengan bab-bab sebelumnya, dan mengantarkan kajian ini
pada bab inti pembahasan. Bagian ini secara khusus menjelaskan bagaimana
budaya Cirebon dan corak budaya Tionghoa serta pergumulan antara kedua budaya
tersebut. Pembahasan ini penting disajikan agar kita mendapat gambaran tentang
setting sosial yang terjadi pada saat itu, dan juga corak budayanya, sehingga
penggunaan ornamen-ornamen Tionghoa yang begitu kuat melekat pada beberapa
budaya material di Cirebon dapat dianalisis secara komprehensif.
A. Mengenal Budaya Cirebon
Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan sistem gagasan,
tindakan, dan hasil karya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.1 Mengacu
pada definisi tersebut, budaya Cirebon merupakan produk dari cipta, karsa dan rasa
manusia Cirebon. Budaya akan terus berkembang karena akan mengakomodir
semua hal yang berkembang dan hidup di daerah tersebut dan juga budaya yang
datang. Budaya Cirebon dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh agama
Islam. Berbagai praktek ritual dari adat Cirebon diwarisi turun temurun dan
dilestarikan sampai sekarang oleh masyarakat Cirebon. Di antara adat yang masih
dilestarikan dan bisa disaksikan adalah Suroan, Saparan, Mauludan,2 Rajaban,
Ruwahan, Syawalan,3 Slametan,
4 Khitanan dan lain sebagainya. Beberpa tradisi
tersebut dianggap oleh masyarakat Cirebon sebagai bagian dari ritual tambahan
yakni ritual agama Islam.
Ritual tambahan sebagaimana di atas, bukan termasuk ibadah dalam makna
yang sempit. Yani mengatakan simbol-simbol budaya itu hanya dimengerti oleh
masyarakat yang bersangkutan, karena pada dasarnya kebudayaaan itu merupakan
reaksi manusia terhadap lingkungannya dan masalah yang dihadapinya. Setiap
daerah atau negara memiliki budaya masing-masing yang mungkin berbeda atau
sama dengan daerah lainnya. Sebagai contoh pemeluk agama yang sama, namun
1Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Yogyakarta: 1981), h. 180-181.
2E. Wijayanto & S. R. Soekarba, ―The Cultural Evolution of Local Islamic Values on
the Muludan Tradition in Cirebon: A Memetics Perspective‖. International Review of
Humanities Studies, vol. 4, no. 2, 2019.; M. Yusuf, ―When Culture Meets Religion: The
Muludan Tradition in the Kanoman Sultanate, Cirebon, West Java‖. Al Albab-Borneo
Journal of Religious Studies (BJRS), vol. 2, no. 1, 2013. 3A. Afghoni, ―Makna Filosofis Tradisi Syawalan (Penelitian Pada Tradisi Syawalan di
Makam Gunung Jati Cirebon)‖. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, vol. 13, no. 1, 2017,
h. 48-64. 4B. Busro & H. Qodim, ―Perubahan Budaya dalam Ritual Slametan Kelahiran di
Cirebon, Indonesia‖. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, vol. 14, no. 2, 2018, h. 127-147.
114
dalam melaksanakan ajaran agamanyabukan ibadah mahdhahberbeda-beda
karena pengaruh budaya lokal masing-masing daerah.5
Cirebon secara semiotik berasal dari kata Caruban. Di dalam naskah Purwaka
Tjaruban Nagari kata Caruban tertulis secara eksplisit yang artinya campuran.
Cirebon dari sejak awal sudah didesain sebagai salah satu pusat masyarakat dan
kebudayaan Islam. Itu dilakukan Ki Somadullah atau lebih populer sebagai
Pangeran Cakrabuana yang mewarisi jabatan Kuwu dari mertuanya atas instruksi
dan perintah dari gurunya Syekh Nurjati. Dengan demikian di bawah bimbingan
Syekh Nurjati, para penguasa Cirebon sudah sejak awal membangun struktur
masyarakat berbasis ajaran Islam, menerapkan hukum Islam meski dengan segala
keterbatasan, membangun basis politik Islam, dan membangun kebudayaan lokal
yang telah mengalami banyak penyesuaian dengan prinsip dan ajaran Islam.
Budaya Cirebon adalah merupakan produk dari cipta, karsa dan rasa
masyarakat Cirebon. Budaya Cirebon khas dan unik, berbeda dengan budaya
lainnya meskipun dari sumber mungkin hampir atau bahkan sama. Sebagai bagian
dari produk sejarah, tentunya harus disadari dalam transmisi mengalami proses
negosiasi dan adaptasi dari waktu ke waktu. Sebagaimana dalam banyak literatur,
budaya Cirebon adalah hasil akulturasi budaya Jawa, Sunda, Tionghoa dan Islam
secara harmonis dan menawan. Kehidupan masyarakat Cirebon berjalan dengan
damai dan tertib berlandaskan prinsip toleransi dan harmonisasi yang
divisualisasikan dalam berbagai wujud budaya material maupun non material.
Cirebon sebagai pelabuhan internasional bisa dikatakan sebagai melting pot
berbagai kebudayaan negara yang pernah berlabuh. Ragam suku, etnis, agama dan
budaya yang berkembang sejak awal munculnya di Nusantara khususnya Cirebon
berimplikasi bagi lahirnya ragam budaya dan produknya sebagaimana tergambar
pada budaya kesenian, tradisi keagamaan, hingga kuliner. Selain itu, hubungan
antara etnis Tionghoa dan Kesultanan Cirebon mengakibatkan terjadinya
pembauran budaya yang dipresentasikan dalam benda-benda bersejarah yang sarat
dengan ornamen Tionghoa. Sebagai Kesultanan Islam, pada perkembangannya
nilai-nilai Islam sangat mewarnai budaya Cirebon.
Islam merupakan elemen utama dalam proses pembentukan identitas budaya
Cirebon dan perkembangannya. Ambary mengatakan bahwa tamaddun Islam
memberikan kontribusi penting terhadap penampakan dan kenampakan keragaman
dan keunikan budaya Cirebon.6 Berbeda jika dibandingkan peran Islam dalam
konteks kebudayaan lokal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Islam berperan sangat
kecil dalam proses pembentukan dan pengembangan budaya lokal. Hal itu terjadi
karena sebelum Islam hadir di kedua tempat itu, sudah ada budaya dan tradisi lokal
yang sangat dominan dan berpengaruh pada masyarakat setempat. Artinya, nilai-
nilai dan prinsip lokal sudah lebih dulu mengakar kuat sebelum datangnya agama-
5A. Yani, ―Pengaruh Islam Terhadap Makna Simbolik Budaya Keraton-Keraton
Cirebon. Holistik, vol. 12, no. 1, 2011, h. 181-196. 6H. M. Ambary, ―Peranan Cirebon sebagai pusat perkembangan dan penyebaran
Islam‖, dalam S. Zuhdi, Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra, (Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan kebudayaan RI, 1996), h. 44.
115
agama, termasuk Islam. Agama-agama yang datang tidak menghilangkan nilai dan
prinsip-prinsip kejawaan mereka.
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Islam berperan penting dalam proses
pembentukan budaya Cirebon. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa
Islam yang ditampilkan adalah Islam yang terbuka, fleksibel, dan menerima adat
istiadat lokal. Di sini prinsip Islam dibahasakan dengan bahasa dan cara pandang
lokal, tetapi tidak kehilangan nilai dan prinsipnya. Hal itu terlihat pada wayang, tari,
gamelan7 dan sebagainya yang banyak dipengaruhi oleh wacana keislaman.
8
Peta politik Cirebon ikut berperan dalam menentukan warna dan wajah budaya
Cirebon. pada masa Sunan Gunung Jati hingga Panembahan Ratu, kedudukan dan
wibawa Cirebon sangat dihormati oleh banyak daerah, teutama Banten dan
Mataram.9 Pasca Sunan Gunung Jati, telah terjadi banyak perubahan disebabkan
konflik internal maupun intervensi eksternal. Pada masa Panembahan Ratu tidak
berbeda jauh dengan masa Sunan Gunung Jati, meski dapat ditemui perbedaan
dalam beberapa aspek. Panembahan Ratu digambarkan sebagai sosok yang soleh,
mencintai kehidupan sufistik dan berwatak Waliyullah. Untuk itu ia tetap
mempertahankan kehidupan agama yang ―asli‖ sebagaimana yang diamalkan
buyutnya, seperti mempertahankan kebiasaan untuk tetap salat Jumat dan salat Idul
Fitri di Masjid Agung Cipta Rasa, serta salat Idul Adha di Masjid Astana di
kompleks pemakaman Gunung Jati.10
Pasca pecahnya Kesultanan Cirebon pada 1677, Vereenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC) mulai memanfaatkan kondisi tersebut dan menanamkan
pengaruhnya. VOC dengan mudah memengaruhi para sultan yang terus berseteru,
sehingga para sultan meminta VOC untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan
konflik internal mereka. Situasi semakin memburuk dengan berhasilnya VOC
memaksakan perjanjian dengan semua kekuatan politik di Cirebon untuk menjadi
penguasa pelabuhan sekaligus memonopoli perdagangan. Bahkan, setelah berhasil
memperkuat monopoli dan basis ekonominya, VOC juga memperkuat intervensi
politik dengan cara mengambil peran dalam menentukan jabatan-jabatan strategis
dalam kesultanan termasuk tentang posisi sultan. Para sultan tidak lagi memiliki
otoritas politik, melainkan tidak lebih sebagai simbol budaya dan agama. VOC
menempati status sosial yang sejajar dengan sultan dan keluarganya, bahkan pejabat
VOC merasa kedudukannya lebih tinggi dibanding sultan dengan status mereka
yang mulai melemah.11
7H. J. Spiller, ―Basic Gamelan Concepts in the Music of Cirebon‖. In Focus: Gamelan
Music of Indonesia, (Routledge, 2010), h. 59-86. 8D. N. Rosyidin dkk., Kerajaan Cirebon, (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah
Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013), h. 197. 9Ambary, ―Peranan Cirebon…, h. 39.
10D. N. Rosyidin, ―Ulama Pasca Sunan Gunung Jati: Jaringan Intelektual Islam
Cirebon Abad ke-16 sampai dengan Abad ke-18‖. Jurnal Sosiologi Walisongo (JSW), vol. 1,
no. 2, 2017, h. 77-194. 11
F. T. Deviani, ―Perjanjian 7 Januari 1681 dan Implikasinya Terhadap Kehidupan
Sosial Politik Ekonomi di Kerajaan Cirebon (1681 M-1755 M)‖. Tamaddun, vol. 4, no. 1,
2016, h. 123-146.
116
Pengaruh VOC yang demikian kuat pada Kesultanan Cirebon berdampak besar
pada eksistensi sultan, serta memengaruhi semua aktivitas masyarakat Cirebon
termasuk kondisi sosial dan budaya. Masyarakat Cirebon yang mayoritasnya
beragama Islam dan mempunyai budaya keraton yang kental, mengalami sedikit
banyak perubahan ketika VOC menguasai wilayah Cirebon. Perubahan itu tidak
hanya terjadi di lingkungan keraton, tetapi juga masyarakat umum baik yang tinggal
di pedalaman maupun pesisir mengalami perubahan sosial dan budaya. Budaya
keraton tidak lagi pure berasal dari tradisi masa lalu, tetapi sudah banyak
dipengaruhi oleh budaya Eropa yg diperkenalkan oleh VOC. Sultan Kasepuhan dan
Kanoman secara sengaja banyak mengadopsi budaya Barat seperti pola perilaku,
tata cara dan model infrastruktur ala Eropa kedalam lingkungan keraton. Akibatnya,
terjadi gap budaya antara budaya keraton yang sudah ―diwarnai‖ Eropa dan budaya
masyarakat umum yang masih sederhana dan cenderung egaliter. Dalam konteks
itu, menurut analisa penulis wibawa keraton menjadi menurun, sekaligus salah satu
penyebab Pangeran Kusumajaya melakukan pemberontakan sebagai bentuk kritik
kepada para sultan.
Cirebon yang bercorak Kesultanan Islam dan memiliki penduduk yang
mayoritas Islam mengalami beberapa perubahan, terutama budaya Cirebon ketika
berada di bawah dominasi Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Perubahan
budaya tersebut terjadi di hampir seluruh aspek kebudayaan Cirebon, yang ditandai
dengan adanya pengaruh budaya asing Eropa di berbagai peninggalan keraton
(infrakstruktur), di samping budaya non fisik yang melekat pada kekuasaan sultan
dalam hal pola perilaku dan pengambilan keputuasan. Kalau kita mengacu pada
teori kebudayaan Koentjaraningrat, bahwa kebudayaan memiliki tujuh unsur, yakni
bahasa, sistem pengetahuan, organisasi politik, sistem peralatan hidup dan
teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi dan kesenian.12
Maka,
penulis melihat beberapa unsur budaya tersebut, juga ikut mengalami perubahan.
Pertama, perubahan dalam budaya organisasi politik. Sebelum kesultanan
terbagi menjadi dua, struktur pemerintahan dipegang oleh seorang sultan sebagai
penguasa tertinggi yang memiliki tugas pokok menjalankan roda pemerintahan.
Sultan biasa dibantu oleh para petinggi kesultanan yang notabene adalah keluarga
atau memiliki garis keturunan dari keluarga Sultan. Namun, ketika VOC menguasai
Cirebon, struktur pemerintahan mengalami perubahan. Aktivitas sultan diawasi oleh
mantri bentukan VOC. Kedudukan sultan sejajar dengan VOC, bahkan secara de
facto kedudukannya di bawah pejabat VOC. Segala kebijakan dan keputusan sultan
harus sepengetahuan dan seijin VOC. Begitu juga sultan dan seluruh masyarakat
Cirebon harus siap menaati setiap aturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan
VOC.13
Kedua, perubahan dalam bidang teknologi dan peralatan hidup. VOC
memperkenalkan saluran air, tempat pembuangan sampah dan limbah kotoran,
pembuatan WC dan pemandian umum. Sehingga Cirebon menjadi lebih bersih dan
12
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, h. 203-204. 13
Deviani, ―Perjanjian 7 Januari 1681 dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial
Politik Ekonomi di Kerajaan Cirebon (1681 M-1755 M)‖, h. 123-146.
117
sehat lingkungannya.14
Menurut Hardjasaputra, awalnya VOC menyediakan air
bersih itu untuk kapal-kapal yang datang ke Cirebon. Penyediaan air bersih itu
diwujudkan pada tahun 1809-1815 dengan dibuatnya saluran air dari sungai Cipager
ke sisi barat Cirebon dan ditampung di bendungan di daerah pasar Balong dan
dialirkan ke pelabuhan. Di samping itu, bahan material yang digunakan untuk
membuat rumah juga mengalami perubahan. Masyarakat Cirebon awalnya
menggunakan bambu kemudian bergeser menggunakan batu dan kayu untuk
membangun temboknya.15
Ketiga, perubahan sistem mata pencaharian. Sebagai kota pelabuhan, banyak
masyarakat Cirebon yang bekerja sebagai nelayan. Mereka menangkap udang untuk
dijadikan terasi dan petis sebagai olahan khas Cirebon. Selain itu, mereka juga
menagkap ikan dan membuat garam.16
Namun, ketika VOC berkuasa dan
menerapkan sistem tanam paksa, maka banyak dari masyarakat yang beralih
menjadi petani. Masyarakat dipaksa untuk menanam hasil pertanian yang laku di
pasaran untuk dijual kembali. VOC lebih menekankan perdagangan dari pada hasil
laut. 17
Keempat, perubahan dalam bidang keagamaan. Kegiatan dakwah dan syiar
Islam mengalami penurunan drastis karena VOC melarang para kyai untuk
melakukan syiar Islam. Aktivitas mubalig di bawah pengawasan VOC, akibatnya
mereka tidak bisa secara leluasa melakukan dakwahnya. Kegiatan dakwah
mengalami penurunan, akibatnya syiar Islam ke wilayah pedalaman mengalami
kendala yang sangat berarti pada saat itu.18
Kelima, perubahan dalam bidang kesenian. Misalnya dalam motif batik
Cirebon. Motif khas batik Cirebon adalah mega mendung yaitu corak berbentuk
awan dan degradasi warna yang menarik. Kehadiran VOC di Cirebon membuat
motif batik menjadi lebih berwarna. Kalau sebelumnya hanya ada motif mega
mendung dan motif Tionghoa, mulai muncul motif kompeni. Adapun ciri motif
kompeni biasanya bergambar tentara kompeni membawa senjata laras panjang atau
senapan, ada juga tentang kehidupan petani dan pedagang.19
Namun, hasil
14
S. T. Sulistiyono, ―Dari Lemahwungkuk hingga Cheribon: Pasang Surut
Perkembangan Kota Cirebon sampai Awal Abad XX‖, dalam S. Zuhdi, Cirebon sebagai
Bandar Jalur Sutra (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI, 1996), h. 139. 15
A. S. Hardjasaputra, Cirebon dalam Lima Zaman: Abad ke-15 hingga
Pertengahan Abad ke-20, (Bandung: Penerbit Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa
Barat, 2011), h. 122. 16
Hardjasaputra, Cirebon dalam Lima…, h. 76. 17
E. P. Hendro, ―Perkembangan Morfologi Kota Cirebon dari Masa Kerajaan Hingga
Akhir Masa Kolonial‖. Paramita, vol. 24, no. 1, 2014, h. 17-30.; Wahyu Iryana,
―Perjuangan Rakyat Cirebon-Indramayu Melawan Imperialisme‖. At-Tsaqafah, vol. 17, no.
2, 2020, h. 373-381. 18
A. S. Hardjasaputra dan T. Haris, (ed.), Cirebon dalam Lima Zaman (Abad ke-15
Hingga Pertengahan Abad ke-20), (Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Barat, 2011), h. 124-125. 19
A. Nursalim, T. R. Rohidi, T. Triyanto, & S. Iswidiarti, ―Batik Wadasan Motif, Past
and Present‖. In Proceeding of International Conference on Art, Language, and Culture,
2017. h. 215-225.; A. S. Patria, ―Dutch Batik Motifs: The Role of The Ruler and The Dutch
Bussinesman‖. Harmonia: Journal of Arts Research and Education, vol. 16, no. 2, 2016, h.
118
penelitian Yani menjelaskan bahwa dalam produk budaya-budaya yang ada di
keraton-keraton Cirebon, pengaruh Islam begitu kuat dan terlihat dalam wujud
budaya fisik maupun pada teks-teks yang tertulis. Teks-teks yang tertulis pada
benda-benda fisik tersebut pada umumnya merupakan penggalan-penggalan ayat al-
Quran seperti yang terlihat dalam bendera kebesaran Cirebon dan piring besar yang
senantiasa dipanggul pada acara panjang jimat.20
Hasil perilaku dan adaptasi manusia umumnya tergambar pada sisa-sisa
bangunan yang ditinggalkan. Adaptasi ialah suatu proses, dan melalui proses itu
hubungan-hubungan yang saling menguntungkan antara suatu organisme dan
lingkungannya dibangun dan dipertahankan.21
Sisa-sisa bangunan di Kesultanan
Cirebon menggambarkan adanya pengaruh unsur-unsur dari suatu kebudayaan
tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan lain. Hal ini memberikan
gambaran kemungkinan adanya kontak budaya antara budaya Tionghoa dan budaya
Cirebon. Keadaan ini diperkuat dengan informasi yang tertulis di dalam Purwaka
Caruban Nagari yang menjelaskan bahwa pada tahun 1415 Cheng Ho dan
pasukannya mendarat di pelabuhan Cirebon.22
Budaya Cirebon yang begitu kaya merupakan hasil proses difusi, akulturasi
dan asimilasi yang berlangsung sangat lama dan intens dari berbagai kebudayaan
yang berasal dari berbagai etnis dan bangsa yang mendiami kota bersejarah ini.
Interaksi antar komunitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menghasilkan
proses pembauran yang berkualitas dan alamiah, pembauran yang meliputi berbagai
dimensi kehidupan. Pembauran yang lama dan terus menerus menghasilkan suatu
masyarakat multikultural. Dengan demikian, penulis melihat budaya Cirebon
muncul dengan karakteristik yang unik.
B. Corak Budaya Tionghoa
Sebelum penulis menjelaskan tentang budaya Tionghoa, penulis terlebih
dahulu akan menguraikan tentang sejarah sebutan Tionghoa. Eddy Lembong
menjelaskan bahwa berdasarkan teks pidato Prof. Dr. A.M. Cecilia Hermina Sutami
pada tanggal 15 oktober 2008 menjelaskan bahwa kata ―Cina‖ berasal dari bahasa
Sansekerta yang berarti ―Daerah yang sangat jauh‖. Cecillia juga mengatakan
bahwa kata ―China‖ sudah ada dalam buku Mahabharata sekitar tahun 1400 SM.
125-132.; T. Borshalina, ―Development of Entrepreneurship and Sustainable Innovation in
Indonesian Small and Medium Enterprises (Study on Trusmi Batik SMEs in Cirebon, West
Java, Indonesia)‖. The 11th Asian Academy of Management International Conference 2015,
(Universiti Sains Malaysia, APEX, Asian Academy of Management, Majelis Profesor
Negara, Yayasan Pahang, 2015). 20
O. I. Hariyanto, ―The Meaning of Offering Local Wisdom in Ritual Panjang
Jimat‖. International Journal of Scientific & Technology Research, vol. 6, no. 6, 2017. 21
D. L. Hardesty, ―The Use of General Ecological Principles in Archaeology‖. In
Advances in Archaeological Method and Theory, vol. 3, (New York: Academic Press,
1980), h. 157-187. 22
Atja, Tjarita Purwaka Tjaruban Nagari, (Jakarta: Ikatan Karyawan Museum, 1972).;
Lihat juga Ma Huan, Ying-yai Sheng-Ian: The Overall Survey of the Ocean's Shores
(1433).Translated by J. V. G. Mills. Edited by Feng Ch‘eng Chun, (Cambridge: The
University Press for the Hakluyt Society, 1970), h. 23.
119
Lebih lanjut Eddy Lembong juga mengatakan bahwa dalam sebuah konferensi yang
diikutinya, Prof. Wang Gungwu menegaskan bahwa orang-orang Cina sendiri tidak
pernah menggunakan istilah ―Cina/China‖. Istilah Cina/China mulai diperkenalkan
oleh bangsa-bangsa Barat di Nusantara sejak awal abad ke-17. Pada awalnya istilah
Cina/China tidak berkonotasi buruk, namun dengan kebijakan penerapan politik
Devide Et Impera yang dicanagkan oleh Belanda, akhirnya istilah itu mengalami
pergeseran makna dan memiliki konotasi yang buruk. Pada awal abad ke-20, Koran
Sin Po yang mewakili orang-orang Cina mengadakan gentleman agreement dengan
para pemuka pergerakan untuk tidak lagi menggunakan istilah Cina/China dan
menggantinya dengan istilah Tionghoa. Itulah sebabnya semua dokumen historis
seperti UUD 1945 dan sebagainya, menggunakan istilah Tionghoa dan bukan
Cina/China. Namun, pasca peristiwa G30SPKI, terbit Surat Edaran Presidium
Kabinet Ampera No. SE.06/Pres.Kab/6/1967 tgl 28 Juni 1967, maka istilah
Cina/China resmi digunakan kembali.23
Peristiwa G30SPKI 1965 berimbas pada eksistensi etnis Tionghoa di
Indonesia. Sejak peristiwa itu pemerintah menutup seluruh surat kabar dan sekolah
yang berbahasa Mandarin. Seperangkat aturan yang cenderung rasispun dikeluarkan
pemerintah di masa Orde Baru, antara lain diharuskannya orang-orang Tionghoa
untuk mengganti nama mereka menjadi lebih Indonesia, serta dilarang merayakan
hari raya orang Tionghoa termasuk juga agama orang-orang Tionghoa. Jadi, pada
masa Orde Baru tidak ada lagi perayaan besar-besaran ketika hari raya Tionghoa
tiba. Akibatnya, generasi muda Tionghoa tidak lagi mengetahui tradisi kebudayaan
leluhur mereka.
Kalau diperhatikan lampiran foto dalam buku Peradaban Tionghoa Selayang
Pandang karya N. J. Lan, menurut penulis sebenarnya Lan ingin menjelaskan
bahwa sebelum masa Orde Baru, etnis Tionghoa dapat melaksanakan penutupan
Tahun Baru Imlek dengan sangat meriah. Uraian Nio tentang kuil-kuil Tionghoa
yang usianya ratusan tahun secara implisit menggambarkan bahwa sebelum masa
Orde Baru, etnis Tionghoa dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan
masyarkat sekitar tanpa masalah.24
Namun, berbagai kebijakan diskriminatif
pemerintah di tahun 1966-1967 terhadap etnis Tionghoa membuat hampir semua
bentuk kebudayaan Tionghoa lumpuh, walaupun secara ekonomi tampak
dimanjakan, namun dalam hal kebudayaan mereka dipasung.25
Barulah, sejak ditandatangani Kepres Nomor 12 tanggal 14 Maret 2014, maka
surat edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28
Juni 1967 resmi dicabut dan tidak berlaku. Dengan berlakunya Kepres Nomor 12
tahun 2014, maka dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,
penggunaan istilah orang atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang
23
Diambil dari: http://www.nabilfoundation.org/artikel/9/istilah-cina-china-dan-
tionghoa . (Diakses pada 30 November, 2020). 24
Nio Joe Lan, Peradaban Tionghoa Selayang Pandang, (Jakarta: Kepustakaan Populer
Gramedia, 2013), h. 204. 25
M. Herwiratno, ―Kelenteng: Benteng Terakhir dan Titik Awal Perkembangan
Kebudayaan Tionghoa di Indonesia‖. Lingua Cultura, vol. 1, no. 1, 2007, h. 78-86.
120
atau komunitas Cina. Sementara untuk penyebutan negara Republik Rakyat China
diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.26
Kebudayaan Tionghoa mempunyai tiga pilar utama, yaitu pers berbahasa
Tionghoa, sekolah-sekolah menengah Tionghoa dan organisasi-organisasi etnis
Tionghoa. Tiga pilar utama itu pada masa Soeharto dihapuskan dengan kebijakan
asimilasinya. Kebijakan Soeharto ini juga membuat orang Tionghoa secara
kebudayaan menjadi ―kurang Tionghoa‖. Kebijakan asimilasi itu berjalan kabur,
dan bahkan kadang-kadang kebijakan politik Soeharto malah cenderung anti
asimilasi. Contohnya adalah pembedaan antara pribumi dan non pribumimembuat
jarak dan sekat itu semakin terlihat, yang justru bertentangan dengan kebijakan
asimilasi yang digalakkan.
Ketika rezim pemerintah berganti, dan BJ Habibi menggantikan Presiden
Soeharto, pintu demokrasi semakin terbuka lebar. Tidak hanya itu, Habibi juga
sangat mengapresiasi bangsa Tiongkok sebagaimana dalam republika.co.id, Habibi
menyatakan bahwa ―hadiah terbesar bangsa Cina (Tiongkok) ke Indonesia adalah
agama Islam‖.27
Bahkan Gus Dur mengatakan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari
tiga ras (Melayu, Austro-Melanesia dan China), sehingga tidak ada keturunan
masyarakat asli. Ketiga ras tersebut yang membentuk kebangsaan Indonesia, bahkan
Gus Dur sendiri adalah keturunan sebagian China dan sebagian Arab.28
Dengan
terbukanya pintu demokrasi di masa Habibi, kebijakan asimilasi Soeharto perlahan-
lahan mulai ditinggalkan dan kebijakan yang lebih pluralis mulai diterapkan
terhadap etnis Tionghoa. Sehingga pada akhirnya, tiga pilar budaya Tionghoa
sebagaimana penulis sebutkan di atas mulai diizinkan kembali sekalipun belum
sepenuhnya.29
Kebudayaan Tionghoa adalah salah satu peradaban tertua di bumi.30
Kebudayaan ini dikenal sejak awal peradaban dunia. Kebudayaan Tionghoa adalah
seluruh hasil cipta, karya serta produk budaya yang dilahirkan masyarakat
Tionghoa, baik masyarakat Tionghoa asli maupun peranakan yang sudah menetap
beberapa generasi di negara lain. Adapun kebudayaan Tionghoa Indonesia adalah
suatu tradisi atau kebiasaan yang hidup dan berkembang serta dipraktekkan oleh
etnis Tionghoa di Indonesia melalui proses penyesuaian dengan budaya lokal
setempat. Ada tiga ajaran yang banyak dipengaruhi oleh kebudyaan Tionghoa, yaitu
26
Kemenkumham, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang
Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Tentang
Ekstradisi (Treaty Between The Republic of Indonesia and the People’s Republic of China
on Extradition), (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016). 27
―Hadiah Terbesar Bangsa Tiongkok ke Indonesia adalah Agama Islam‖. Didapatkan
dari: https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/13/09/27/mtrx43-habibie-
hadiah-terbesar-bangsa-cina-ke-indonesia-adalah-islam. (Diakses tanggal 17 Agustus 2020). 28
Ali Mustajab, ―Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia‖.
IN RIGHT, vol. 5, no. 1, 2015, h. 153-193. 29
L. Suryadinata, ―Kebijakan Negara Indonesia Terhadap Etnik Tionghoa: Dari
Asimilasi Ke Multikulturalisme ?‖. Antropologi Indonesia, no. 71, 2003, h. 1-12. 30
C. Gan, ―Archaeological Finds and Origins of Chinese Civilization‖. In A Concise
Reader of Chinese Culture, (Singapore: Springer, 2019), h. 1-19.
121
ajaran Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme.31
Ketiga ajaran tersebut dijadikan
masyarakat Tionghoa sebagai landasan dan pedoman dalam berperilaku dan
mengatur tata kehidupan mereka sehari-hari.32
1. Taoisme
Masyarakat Tionghoa meyakini Taoisme sebagai ajaran yang bisa
mendatangkan keberkahan dalam kehidupan manusia. Mereka mengamalkan ajaran
Tao dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menjadikan ajaran Lao Tze sebagai
pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara, serta dalam hal memimpin dan
manajemen. Dalam manajemen Tao misalkan, manusia diajarkan agar kreatif, dan
kreativitas itu menjadi salah satu budaya Tionghoa yang masih bisa disaksikan
sampai sekarang.33
Secara historis, Taoisme merupakan ajaran yang berkembang sejak 300 SM.
dibawa oleh Lao Tzu. Melalui ajaran ini Lao Tzu mengatakan seluruh jagad alam
raya dan isinya merupakan manifestasi dan refleksi dari Tao yang sempurna. Semua
aksi yang dijalankan manusia merupakan pemberian Tao. Dengan kata lain, Tao
adalah segala-galanya dalam kehidupan. Lao Tzu menulis sebuah buku Tao te
Ching, sebuah buku hikmat yang kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup
masyarakat Tionghoa. Buku tersebut terdiri atas tiga topik, yaitu: 1) Hukum alam,
berisi penjelasan tentang bagaimana segalanya terjadi. 2) Cara hidup, memuat
penjelasan tentang bagaimana caranya hidup dalam keharmonisan yang disadari
dengan hukum alam. 3) Metode kepemimpinan, berisi penjelasan tentang
bagaimana caranya memerintah atau mendidik orang lain menurut hukum alam.34
Pada dasarnya, ajaran Taoisme sebagaimana yang diamalkan etnis Tionghoa
sangat menekankan keselarasan perkembangan unsur-unsur fisik, sosial dan
spiritual serta kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari.35
Manusia diajarkan
31
Q. H. Vuong, Q. K. Bui, V. P. La, T. T. Vuong, V. H. T. Nguyen, M. T., Ho,... & M.
T. Ho, ―Cultural Additivity: Behavioural Insights from the Interaction of Confucianism,
Buddhism and Taoism in Folktales‖. Palgrave Communications, vol. 4, no. 1, 2018, h. 1-
15.; H. Liang, ―Jung and Chinese Religions: Buddhism and Taoism‖. Pastoral
Psychology, vol. 61, no. 5-6, 2012, h. 747-758.; L. Silong, ―Threes Types of Confluence
among Confucianism, Buddhism and Taoism‖. Journal of Peking University (Philosophy &
Social Sciences), vol. 2, 2011. 32
L. Hao, ―Goodness: The Ultimate Integration of Confucianism, Buddhism and
Taoism in China‖. In Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy, vol. 12,
2018, h. 143-147. 33
Y. U. A. N. Ming-ze, ―A Survey on the Relationship History between Buddhism and
Taoism in Southeast Guangxi‖. Journal of Yulin Normal University, no. 1, 2016, h. 5. 34
F. Yang, ―Taoist wisdom on individualized teaching and learning—Reinterpretation
through the perspective of Tao Te Ching‖. Educational Philosophy and Theory, vol. 51, no.
1, 2019, h. 117-127.; M. Daoshan, ―The Distribution and Feature Checking of Interrogative
Sentences in Tao Te Ching‖. Linguistics, vol. 4, no. 6, 2016, h. 230-236.; Y. Tang, ―On the
Dao De Jing (Tao Te Ching)‖. In Confucianism, Buddhism, Daoism, Christianity and
Chinese Culture, (Berlin, Heidelberg: Springer, 2015), h. 153-157. 35
Y. Guoqing, ―History of Taoism‖. Rituals and Practices in World Religions: Cross-
Cultural Scholarship to Inform Research and Clinical Contexts, vol. 5, 2019, h. 99-112.; N.
122
bagaimana bisa hidup secara harmonis dengan manusia lain dan alam. Menurut
ajarannya, manusia baru dapat mengelola alam setelah dia dapat hidup bersahabat
dengan alam. Jika dilihat dari perspektif Islam, maka ini berkaitan dengan tugas
manusia sebagai khalifah (wakil Allah di bumi)36
sebagaimana dalam al-Qur‘an
surat Al-A‘raf [7] ayat 56. Ayat ini menjelaskan bahwa sebagai khalifah, manusia
diberi tugas untuk membangun, mengelola dan memakmurkan alam sesuai dengan
kehendak Allah. Jadi, dalam menjalankan fungsinya manusia harus bisa bersahabat
dengan alam dan tidak merusaknya.
2. Konfusianisme
Ajaran kedua setelah Taoisme adalah Konfusianisme. Ajaran ini dibawa oleh
Konghucu, serta lahir dan berkembang di Tiongkok.37
Banyak orang Tionghoa, baik
yang berada di Tiongkok maupun perantauan mengikuti ajaran Konghucu. Ajaran
ini sangat popular dan banyak mendapat pengikut dibanding ajaran lainnya. Ajaran
Konghucu dan budaya Tionghoa sempat ―dibekukan‖ selama masa Orde Baru.38
Namun, pasca reformasi, ajaran ini dihidupkan kembali untuk dianut oleh
masyarakat, bahkan budaya Tionghoa boleh ditampilkan kembali di depan umum.
Dalam praktiknya, ajaran Konfusius mengatur moral kehidupan manusia, baik
hubungan manusia dengan sesamanya seperti hubungan keluarga, suami-istri, anak-
anak, juga mengatur hubungan antara negara dan masyarakat. Salah satu di antara
ajaran Konghucu adalah yang berkaitan dengan etika, mereka menyebutnya Sang
Kang (tiga hubungan tata krama), yaitu hubungan seorang raja dengan menterinya
atau hubungan atasan dan bawahan, hubungan ayah dengan anak, serta hubungan
suami dan istri.39
Ajaran Konghucu sangat menekankan prinsip kemanusiaan. Manusia harus
kembali pada sifat kemanusiaannya yang sejati agar sejahtera lahir batin dan
beradab. Sama halnya dengan ajaran moral Konfusius yang juga mengajarkan
keharmonisan dengan sesama manusia, terutama antara anak dan orang tua. Seorang
anak harus hormat dan tunduk pada orang tua bagaimanapun kondisi orang tua. Jati
diri seorang anak dibuktikan dari kepatuhannya pada orang tua. Begitu pula
hubungan atasan dan bawahan, raja dan rakyatnya diatur dalam Konghucu.40
Di
K. Okoro, ―Oriental Traditions [Taoism]: A Critical Option for Peace Building Initiative in
the Contemporary Society‖. Journal of Social Research, vol. 1, no. 4. 2017. 36
C. Kersten, ―The Caliphate‖. In Oxford Research Encyclopedia of Religion, 2019.; A.
Alajmi, ―‗Ulama and Caliphs New Understanding of the ―God's Caliph‖ term‖. Journal of
Islamic Law and Culture, vol. 13, no. 1, 2011, h. 102-112. 37
T. A. Wilson, ―Culture, Society, Politics, and the Cult of Confucius‖. On Sacred
Grounds: Culture, Society, Politics, and the Formation of the Cult of Confucius, 2020, h. 7. 38
T. E. Muas, ―Restoring Trusts without Losing Face: An Episode in the History of
China–Indonesia Relationship‖. Tawarikh, vol. 6, no. 2, 2015.; M. S. Heidhues, ―Studying
the Chinese in Indonesia: A long half-century‖. SOJOURN: Journal of Social Issues in
Southeast Asia, vol. 32, no. 3, 2017, h. 601-633. 39
X. I. E. Yuhan, & G. E. Chen, ―Confucius‘ Thoughts on Moral Education in
China‖. Cross-Cultural Communication, vol. 9, no. 4, 2013, h. 45-49. 40
L. Bi, J. Ehrich, & L. C. Ehrich, ―Confucius as Transformational Leader: Lessons for
ESL Leadership‖. International Journal of Educational Management, vol 26, no. 4, 2012,
123
samping prinsip etika,41
Konghucu juga mengajarkan lima sifat mulia yang biasa
disebut Wu Chang yang harus dimiliki manusia, yaitu: 1) Ren/Jen; cinta kasih, rasa
kebenaran, kebajikan, tahu diri, halus budi pekerti, rasa tepo seliro dan dapat
menyelami perasaan orang lain. 2) I/Gi; rasa solidaritras, senasib sepenanggungan
dan membela kebenaran. 3) Li/Lee; sopan santun, tata krama dan budi pekerti. 4)
Ce/Ti; bijaksana atau kebijaksanaan, pengertian dan kearifan. 5) Sin; kepercayaan,
rasa untuk dapat dipercaya oleh orang lain, serta dapat memegang janji dan
menepati janji.42
3. Buddhisme
Agama Buddha (Buddhism) adalah sebuah ajaran yang banyak dianut oleh
etnis Tionghoa di negeri mereka, juga di perantauan. Secara historis, agama Buddha
merupakan warisan peradaban kuno dari India. Ajaran agama ini mengajarkan agar
menjunjung tinggi dan menghargai hak asasi wanita sekaligus menghilangkan
kasta-kasta yang ada pada masa itu. Di samping itu, ajaran Buddha juga sangat
menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Ajaran Buddha menekankan kefanaan pada semua benda. Khayalan, ketidak-
kekalan, dan sifat tidak sejati dari keakuan, serta persamaan dan persaudaraan
semua makhluk. Menurut ajaran ini, jalan untuk sampai pada Sang Buddha itu tidak
mudah, butuh perjuangan dan kerja keras, serta disiplin, yakni melalui meditasi dan
perenungan yang tinggi sekaligus mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Menjaga hubungan yang baik dan mengembangkan cinta kasih di antara sesama
manusia agar terwujud hubungan yang harmonis.43
Ajaran Buddha juga sangat
menekankan kebebasan berfikir yang implikasinya adalah sangat menghargai dan
menghormati semua ajaran agama yang ada. Sikap menghormati ini merupakan
manifestasi dari spiritual yang tinggi.44
Pengaruh Buddhisme pada masyarakat Tionghoa dapat dilihat dalam praktik
meditasi, hidup disiplin, dan hubungan baik sesama manusia, terutama dengan
sesama etnis Tionghoa. Demikian juga kasih sayang sesama keluarga dan saling
membantu antara teman merupakan perwujudan dari pengaruh Buddhisme dan
391-402.; S. S. Wah, ―Confucianism and Chinese Leadership‖. Chinese Management
Studies, vol. 4, no. 3, 2010, h. 280-285. 41
X. Ke, ―Person-making and Citizen-Making in Confucianism and their Implications
on Contemporary Moral Education in China‖. Re-envisioning Chinese Education: The
Meaning of Person-making in a New Age, (London: Routledge, 2015), h. 116-129. 42
D. N. Anna, ―Konghucu di Korea Kontemporer dan Sumbangannya Terhadap
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia‖. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, vol. 12, no. 2,
2016, h. 239-254. 43
S. Y. Wang, Y. J. Wong, & K. H. Yeh, ―Relationship Harmony, Dialectical Coping,
and Nonattachment: Chinese Indigenous Well-being and Mental Health‖. The Counseling
Psychologist, vol. 44, no. 1, 2016, h. 78-108.; G. Xing, ―Conflict and Harmony between
Buddhism and Chinese Culture‖. International Journal of Buddhist Thought and
Culture, vol. 25, 2015, h. 83-105. 44
F. Hassan, ―A Comparative Approach to Common Ground between Buddhism and
Islam‖. European Journal of Scientific Research, vol. 71, no. 4, 2012, h. 514-519.
124
Konfusianisme.45
Ketiga ajaran yakni Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme
sangat mewarnai kehidupan etnis Tionghoa, baik di negeri mereka maupun
perantauan. Hingga kini, ketiga ajaran tersebut telah melekat dalam kehidupan
orang Tionghoa.
Kebudayaan dan peradaban Tiongkok dimulai dari sungai kuning. Bangsa
Tiongkok selama berabad-abad bergaul dan berinteraksi dengan suku lainnnya di
Tiongkok, sehingga terbentuk kebudayaan Tionghoa. Ada 56 etnis berbeda di
Tiongkok, mereka saling berinteraksi, berintegrasi dan beradaptasi sehingga
membentuk kebudayaan Tionghoa.46
Mereka disebut bangsa Han. Selain bangsa
Han, di Tiongkok juga ada bangsa lain seperti bangsa Tibet, Bai, Mongol, Kazakh
dan Uighur. Kazakh dan Uighur pada umumnya beragama Islam. Mereka hidup
berdampingan dan membentuk bangsa yang besar dan kebudayaan serta peradaban
yang tinggi.47
Masyarakat Tionghoa juga terdiri atas banyak marga, kemudian membentuk
satu kesatuan yang akrab. Marga merupakan salah satu keunikan sekaligus
kebanggan bagi mereka. Bagi masyarakat Tionghoa primitif, yaitu pada masa awal
kebudayaan Tionghoa, anak-anak mengikuti marga ibunya yang disebut Xing
karena mereka tidak mengetahui siapa ayahnya. Dalam konteks ini, sang ibu
merupakan figure central dalam keluarga yang dapat membentuk karakter anak,
sebab ibu yang merawat dan mendidik anaknya. Jadi dalam masyarakat Tionghoa
primitif, mereka menganut paham matriarkhal.48
Pada perkembangan berikutnya setelah kebudayaan semakin maju dan laki-laki
menjadi pekerja utama, maka terjadi alih peran, yakni posisi ibu digantikan oleh
ayahnya. Simbol kebanggan dan kekuatan dalam keluarga adalah ayah, karena ayah
yang mencari nafkah dan menghidupi keluarganya. Masyarakat Tionghoa
mengambil marga dari garis ayahnya atau umum disebut Patriarkhal. Penciptaan
marga dalam masyarakat Tionghoa berbeda-beda. Ada yang menggunakan totem,
nama wilayah, gelar kebangsaan, maupun nama negara.49
Kebudayaan Tionghoa adalah sebuah kebudayaan yang banyak menyimpan
khazanah tentang simbol yang penting dan bermakna bagi kehidupan mereka.
Dalam peradaban Tiongkok, simbol-simbol itu sudah dikenal sejak ribuan tahun
yang lalu dan bertahan sampai saat ini. Sehingga itu, tidak heran jika simbol
merupakan karakteristik peradaban Tiongkok yang memiliki banyak makna. Bagi
etnis Tionghoa, di mana dan kapan saja, simbol merupakan harapan dan berkah dari
kehidupan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Tionghoa juga tidak bisa
lepas dari simbol sebagai sebuah anugerah dan motivasi dalam beraktivitas sehari-
45
M. D. Coogan, Eastern Religions: Hinduism, Buddhism, Taoism, Confucianism,
Shinto, (Duncan Baird Publishers, 2005), h. 552. 46
R. Hayhoe, ―Encountering Chinese Culture Over Changing Times‖. Education
Journal, vol. 47, no. 2, 2019, h. 1-22. 47
J. P. Dorian, B. Wigdortz, & D. Gladney, ―Central Asia and Xinjiang, China:
Emerging Energy, Economic and Ethnic Relations‖. Central Asian Survey, vol. 16, no. 4,
1997, h. 461-486. 48
L. Xiaoxiang, Origins Chinese People and Customs, (Jakarta: Elex Media
Komputindo, 2003), h. 32. 49
Xiaoxiang, Origins Chinese…, h. 34.
125
hari. Simbol-simbol kuno dalam kebudayaan tidak hanya sekedar motif-motif
hiasan belaka, bukan sekedar ―seni untuk seni‖, tetapi motif mengandung makna
yang dalam dan merupakan motif magis religious.50
Ternyata bagi orang Tionghoa,
selain sebagai seni dan hiasan dinding, simbol bisa menjadi motif yang dapat
mencerahkan kehidupan mereka sekaligus menjadi harapan bagi kelangsungan
hidup bangsa Tiongkok. Lebih jauh lagi, simbol bagi masyarakat Tionghoa ternyata
menjadi pandangan hidup, baik dalam aspek politik, ekonomi dan sosial, serta
dalam keagamaan mereka.
Kebudayaan Tionghoa menyimpan kekayaan simbol-simbol yang telah
diamalkan oleh masyarakat Tionghoa sejak ribuan tahun yang lalu. Simbolisme
merupakan ciri khas yang akan terus melekat pada etnis Tionghoa dimanapun
berada dan sampai kapanpun. Simbol itu bisa mengungkapkan perasaan maupun
makna tertentu bagi kehidupan sehari-hari orang Tionghoa. Masyarakat Tionghoa
juga percaya kalau simbol bisa membawa berkah bagi kehidupan mereka. Simbol-
simbol itu bisa berupa gambar, alam, manusia maupun binatang.51
Di antara simbol-
simbol itu, simbol hewan mendapat prioritas dalam kehidupan tradisional
masyarakat Tionghoa. Simbolisme hewan mendapat perhatian utama dan memiliki
makna yang penting bagi keberlangsungan hidup mereka. Hewan-hewan yang
banyak mereka jadikan simbol adalah singa, kuda, ular, dan naga. Dalam
kepercayaan mereka, kebudayaan yang disimbolkan dengan hewan-hewan dapat
meramalkan masa depan, harapan maupun tantangan.
Berdasarkan hal di atas, Konfusius pernah mengemukakan sebagaimana
dikutip Herwiratno bahwa kata-kata tidak bisa mengungkapkan kedalaman bahasa,
dan bahasa tidak mampu mengungkapkan kedalaman arti. Maka, tidak heran jika
bangsa Tiongkok banyak mengungkapkan sesuatu dengan simbol. Simbol-simbol
yang sarat makna banyak ditemukan di Klenteng. Di depan, kanan dan kiri
Klenteng biasanya ada sepasang arca singa yang bermakna penolak mara bahaya.
Patung sepasang naga biasanya ditemukan di atap Klenteng yang melambangkan
perlindungan, kekuasaan dan keberuntungan. Naga ikan atau Long Yu bermakna
ketekunan dan kerja keras dalam meraih keberhasilan. Burung Phoenix (Hong)
sering dipasangkan dengan naga yang bermakna keserasian dan keseimbangan Yin
Yang. Hewan Qilin sebagai lambang kebajikan sempurna, umur panjang, kebesaran,
kepatuhan, keturunan yang cemerlang dan pemerintahan yang bijak. Kura-kura
perlambang umur panjang dan bermartabat. Simbol itu tidak hanya ada di hewan,
tetapi juga beberapa tumbuhan dan buah-buahan memiliki makna. Misalnya teratai
lambang kesucian, buah apel lambang keselamatan, jeruk simbol rejeki
keberuntungan dan pohon pisang sebagai lambang harapan akan banyaknya
keturunan.52
Bicara tentang identitas dan budaya Tionghoa akan sangat dipengaruhi oleh
latar belakang sejarah, adat istiadat, bahasa, geografi, dan karakteristik etniknya dari
mana identitas budaya itu berasal termasuk juga politik dan kekuasaan yang sedang
50
Ong Hean Tatt, Simbolisme Hewan Cina, (Jakarta: Kesaint Blanc, 1996), h.1. 51
D. Zhang, ―Cultural Symbols in Chinese Architecture‖. Architecture and Design
Review, vol. 1, 2018, h. 1-19. 52
Herwiratno, ―Kelenteng: Benteng Terakhir…, h. 78-86.
126
berkuasa. Dialek bahasa Tionghoa yang diucapkan oleh sekelompok orang juga
menunjukkan perbedaan kebudayaan mereka. Perbedaan budaya itu terutama
kelihatan sekali dalam budaya material, budaya makan, adat istiadat, budaya
pemakaman yang semuanya itu menunjukkan perbedaan pandangan kelompok
tersebut dengan kelompok lainnya. Wang Gungwu dalam Christian mengatakan
budaya Tionghoa mudah beradaptasi dengan bahasa, budaya dan agama Barat.53
Sementara Hall mengatakan identitas budaya itu tidak tetap, semuanya
tergantung bagaimana memosisikan (positioning) dan diposisikan, dan menjadi
subyek sejarah, budaya, serta kekuasaan yang terus berlangsung. Identitas budaya
merupakan suatu proses yang tidak akan pernah selesaiselalu dalam proses
identifikasi dalam konteks sejarah dan budaya.54
Di dunia yang semakin maju dimana mobilitas masyarakat semakin tinggi,
Joseph mengatakan saling ketergantungan ekonomi antar negara tidak dapat
dielakkan, perubahan pola imigrasi dan politik yang begitu dinamis membutuhkan
pemahaman atas kultur yang berbeda-beda. Dengan kata lain, komunikasi antar
budaya menjadi penting.55
Senada dengan Joseph, Liliweri mengatakan bahwa
dalam hidup bermasyarakat menuntut seseorang untuk mau berkomunikasi, baik
dengan anggota kelompoknya maupun dengan orang diluar kelompoknya. Dalam
komunikasi antar kelompok sesungguhnya terdapat proses interaksi dan komunikasi
antar budaya, serta antar masing-masing individu yang memiliki latar belakang
kebudayaan yang berbeda.56
Pemerintah Indonesia ingin membentuk masyarakat yang memiliki sense of
belonging terhadap bangsanya, apapun etnisnya di tengah kemajemukan yang ada,
sebuah bangsa yang memiliki kepemilikan bersama, yakni satu bangsa, satu tanah
air dan satu bahasa. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan
kebijakannya itu adalah dengan mengasimilasikan dan meleburkan etnis Tionghoa
ke dalam penduduk pribumi Indonesia. Suryadinata menilai upaya asimilasi tersebut
menghadapi kendala karena begitu besar populasi Tionghoa ke Asia Tenggara
termasuk Indonesia setelah paruh abad ke-19.57
Namun, sepanjang kebijakan
pemerintah terhadap etnis Tionghoa tidak diskriminatif, penulis optimis etnis
Tionghoa akan lebih berorientasi terhadap negara dimana mereka tinggal walau
kebangkitan kembali ke Tiongkok menguat. Identifikasi budaya mereka dengan
Tionghoa akan menipis dan mereka akan terus menyesuaikan diri dengan
lingkungan sekitarnya.
Peranan orang Tionghoa dalam penulisan sejarah Indonesia dalam berbagai
aspek kurang ditonjolkan, sekalipun bukti sejarah menunjukkan mereka memiliki
53
S. A. Christian, ―Identitas Budaya Orang Tionghoa di Indonesia‖. Cakrawala
Mandarin, vol. 1, no. 1, 2017, h. 12-14. 54
Stuart Hall, ―Cultural Identity and Diaspora‖, dalam Jonathan Rutherford, (eds.),
Identity: Community, Culture, Difference, (London: Lawrence and Wishartm, 1990), h. 225. 55
A. D. Joseph, Komunikasi Antar Manusia, (Jakarta: Professional Books, 1997), h.
482. 56
A. Liliweri, ―Prasangka Sosial dan Efektivitas Komunikasi Antar Etnik di Kupang‖.
Dalam A. Liliweri (ed.), Perspektif pembangunan: Dinamika dan tantangan pembangunan
Nusa Tenggara Timur, (Kupang: Penerbit Yayasan Citra Insan Pembaru, 1994), h. 56. 57
Suryadinata, ―Kebijakan Negara Indonesia…, h. 1-12.
127
sumbangsih dan peran serta bagi perkembangan Indonesia, baik dalam bidang
keagamaan, kesusasteraan, kesenian, bahasa, olahraga, bangunan, kuliner maupun
kedokteran. Sebaliknya, gambaran umum atau stigma yang berlaku di tengah
masyarakat pribumi adalah stigma negatif, bahkan mereka dianggap sebagai
economic animal yang bersifat oportunis, nasionalismenya diragukan, mereka
dianggap egois, dan loyalitas politiknya diragukan.58
Etnis Tionghoa yang ada di Indonesia menurut Hanggara terbagi menjadi tiga
kelompok, yaitu: kelompok yang ingin tetap menjaga ikatan politik dan budaya
dengan Tiongkok; kelompok yang hanya ingin memelihara ikatan budaya; dan
kelompok yang melepaskan diri dari ikatan budaya maupun politik dengan
Tiongkok.59
Kelompok atau etnis Tionghoa Indonesia bahkan turut memberikan
solusi untuk mengatasi problem sosial agar hubungan antara masyarakat Indonesia
dan etnis Tionghoa tidak ada gap dan stigma negatif, serta terwujud hubungan yang
harmonis dan rukun. Berbagai usulan yang diberikan untuk mengatasi masalah-
masalah ini begitu beragam; ada yang mengusulkan integrasi politik; ada juga yang
menyarankan pembauran total sebagai solusi; dan ada juga yang mengusulkan
masuk Islam.
Peran orang-orang Tionghoa dalam kedatangan Islam di Indonesia telah
memicu perdebatan di kalangan akademisi. Secara umum pendapat yang populer
adalah dunia Arab berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, bukan
Tionghoa. Pedagang Arab dan Persia yang pertama kali memperkenalkan Islam ke
Nusantara, mendirikan komunitas pedagang Muslim asing di kota-kota pelabuhan di
seluruh Nusantara. Pendapat populer ini ditentang oleh beberapa sarjana yang
berpendapat bahwa Tionghoa juga berperan penting dalam penyebaran Islam di
Indonesia, terutama pada abad XV dan XVI melalui perdagangan. Kelompok ini
diwakili oleh Parlindungan, Slamet Muljana dan Al Qurtuby. Namun, pandangan Al
Qurtuby selangkah lebih maju dengan mengidentifikasi Laksamana Cheng Ho
sebagai tokoh kunci. Menurutnya, banyak Muslim dari Canton, Chang-chou dan
Ch‘uan-chou yang mengikuti ekspedisi Cheng Ho ke Jawa dan bermukim di kota-
kota pesisir utara Jawa seperti Gresik, Tuban, Surabaya, Semarang, Cirebon, Jakarta
dan Banten.60
Al Qurtuby juga memperkuat argumennya dengan menggunakan
empat sumber sejarah: Pernyataan dari petualang asing;61
catatan-catatan Tionghoa;
teks tertulis dan tradisi lisan Jawa; bangunan-bangunan bersejarah dan monumen
yang ditemukan di Jawa. Beberapa historiografi Jawa seperti Babad Tanah Djawi,
Serat Kandaning Ringgit Purwa, Carita Lasem, Babad Cirebon dan Hikayat
58
Khong Yuanzhi, Silang Budaya Tiongkok-Indonesia, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,
2005). 59
A. Hanggara, ―Nasionalisme Etnis Tionghoa di Indonesia‖. Jurnal Equilibrium, vol.
14, no. 02, 2016, h. 71. 60
S. Al Qurtuby, ―The Imprint of Zheng He and Chinese Muslims in Indonesia‘s Past‖.
Zheng He and the Afro-Asian World, h. 171-186. 61
S. Al Qurtuby menggunakan kesaksian Ma Huan dari Cina, Loedewicks dari Belanda
dan Ibnu Batutah dari Magribi.
128
Hasanuddin juga dikutip Al Qurtuby untuk memperkuat peran orang Tionghoa
dalam islamisasi di tanah Jawa.62
Pengaruh Tionghoa dapat dilihat di beberapa masjid di Jawa, masjid Cheng Ho
misalnya. Muzzaki63
mengatakan bahwa masjid seharusnya tidak hanya berfungsi
sebagai tempat ibadah, namun juga berfungsi sosial. Rohman mengatakan bahwa
itulah yang dilakukan oleh masjid Cheng Ho, yang tidak hanya dijadikan sebagai
tempat salat sehari-hari orang Islam, namun juga membangun hubungan sosial,
persatuan umat dan juga bisa sebagai tempat mempromosikan proses asimilasi dan
harmoni antar umat beragama di Indonesia.64
Masjid Cheng Ho juga merupakan
sebuah wadah bagi Tionghoa Muslim untuk mengekspresikan identitas budaya dan
sosial politik, sekaligus membantu mereka untuk membangun perekonomian
dengan aman tanpa adanya intimidasi dari manapun. Dari masjid ini pula, etnis
Tionghoa Muslim bisa menjalin hubungan yang baik dengan organisasi
kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah yang membuat mereka semakin
merasa aman secara sosial politik. Menurut Mahfud masjid Cheng Ho juga harus
berperan aktif untuk merekatkan harmoni antara orang-orang Tionghoa khususnya,
dan etnis Tionghoa Muslim pada umumnya dengan penduduk pribumi.65
Sementara
Muzakki mengatakan bahwa konflik yang banyak terjadi di berbagai belahan dunia
karena kaum minoritas ini kurang mampu bernegosiasi dengan budaya lokal.66
Dan
ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Ketimpangan ekonomi dan sosial
dan persaingann politik menjadi lahan subur untuk timbulnya konflik sosial antara
komunitas Tionghoa dan penduduk lokal. Bernegosiasi dengan budaya lokal bukan
berarti kehilangan identitas budanya. Komunitas Tionghoa bisa tetap memperkuat
identitas budayanya di masjid Cheng Ho.67
Kebudayaan itu sifatnya dinamis dan akan selalu mengalami perubahan dan
perkembangan. Budaya tidak hanya mencakup produk, namun meliputi suatu proses
yang tumbuh kembang bersama rasionalitas lain. Pertemuan antar budaya yang
berbeda akan menghasilkan hibriditas kebudayaan yang sulit sekali dikenali batas-
batasnya. Boleh jadi juga akan melahirkan kebudayaan baru yang akan lebih
cenderung kepada budaya mainstream, atau bisa juga lebih condong kepada budaya
marginal. Hibriditas budaya itu bisa disaksikan dalam kehidupan sosial masyarakat
62
S. Al Qurtuby, Arus Cina-Islam-Jawa: Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa
dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV&XVI, (Yogyakarta: Inspeal
Ahimsya Karya Press, 2003), h. 39-41. 63
Muzzaki, ―Cheng Hoo Mosque…, h. 1-29. 64
A. Rohman, ―Chinese–Indonesian Cultural and Religious Diplomacy‖. Journal of
Integrative International Relations, vol. 4, no. 1, 2019, h. 1-24. 65
C. Mahfud, ―The Role of Cheng Ho Mosque: The New Silk Road, Indonesia-China
Relations in Islamic Cultural Identity‖. Journal of Indonesian Islam, vol. 8, no. 1, 2014, h.
23-38. 66
A. Muzakki, ―Ethnic Chinese Muslims in Indonesia: An Unfinished Anti-
Discrimination Project‖. Journal of Muslim Minority Affairs, vol. 30, no. 1, 2010, h. 81-96. 67
R. Rahmawati, K. Yahiji, C. Mahfud, J. Alfin, & M. Koiri, ―Chinese Ways of Being
Good Muslim: Fom the Cheng Hoo Mosque to Islamic Education and Media
Literacy‖. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, vol. 8, no. 2, 2018, h. 225-
252.
129
seperti bahasa, ritual keagamaan, dan pandangan hidup. Proses hibriditas itu bisa
terjadi melalui hubungan sosial dan perkawinan silang budaya. Hubungan yang
terakhir ini menurut Humaedi adalah yang paling efektif. Perkawinan silang budaya
akan menghasilkan pembauran dalam berbagai aspek. Aspek bahasa misalnya,
akan ada bahasa yang unik di dalam keluarga disebabkan karena pernikahan. Bisa
jadi keluarga tersebut memilih bahasa kebudayaan mainstream ataupun tidak
memilih bahasa kedua pasangan, namun memilih bahasa Indonesia.68
Beberapa pemimpin Tionghoa Muslim telah membentuk identitas yang khas
melalui hubungan trans nasional dengan Muslim di Tiongkok dan
mengonfigurasinya kembali dalam konteks Indonesia. Imajinasi trans-nasional ini
bukan bentuk keinginan untuk kembali atau terikat dengan negeri Tiongkok, tetapi
lebih merupakan upaya untuk mendefinisikan kembali posisi sosial Tionghoa
Muslim di Indonesia. Penulis melihat upaya tersebut sangat wajar, sebab sejak
dahulu Tionghoa memiliki hubungan yang erat dengan penduduk pribumi
Nusantara yang dalam konteks ini Indonesia. Setiono mengatakan bahwa sejak abad
1-6 SM. yakni pada masa pemerintahan Kaisar Wang Ming atau Wang Mang, etnis
Tionghoa telah mengenal Nusantara dengan nama Huang-Tse. Jarak tempuh
Tiongkok-Nusantara yang jauh memerlukan waktu tempuh satu tahun lamanya, hal
itu disebabkan karena pengaruh musim, mereka menggunakan angin muson yang
berubah setiap enam bulan sekali untuk berlayar. Menyebabkan banyak orang
Tionghoa yang menetap dan kemudian menikahi penduduk Nusantara hingga
memiliki keturunan yang kemudian disebut oleh sebagian orang sebagai Tionghoa
Peranakan.69
C. Pergumulan Budaya Tionghoa dan Budaya Cirebon
Pada bagian ini akan dijelaskan pembauran budaya Tionghoa dan budaya
Cirebon. Sejak awal kedatangan etnis Tionghoa ke Cirebon, mereka sudah
membaur dengan masyarakat setempat dalam berbagai aspek kehidupan. Hasilnya
dapat dilihat dari adanya pembauran alami dalam kehidupan mereka. Etnis
Tionghoa telah menyatu dengan penduduk setempat dan mengalami pembauran,
salah satunya melalui pernikahan. Oleh sebab itu, sebagian besar penduduknya
sudah menjadi penduduk peranakan, lahir dan menetep di Indonesia, khususnya
Cirebon.70
Berbagai kesenian dan upacara tradisi terus dijaga dan dilestarikan
masyarakat atau etnis Tionghoa di Cirebon, salah satu contohnya adalah upacara
Imlek untuk menyambut datangnya tahun baru dengan dimeriahkan oleh beberapa
jenis kesenian atau pertunjukkan seperti Barongsai, Liong dan sebagainya.
Kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia khususnya Cirebon harus diakui
membawa tradisi, tata kehidupan dan norma-norma sebagaimana yang berlaku
dalam masyarakat asal mereka, serta sikap fanatisme terhadap tradisi negara
leluhur. Hari S. Gani sebagaimana dikutip Sopiah mengatakan bahwa dalam
68
M. A. Humaedi, ―Budaya Hibrida Masyarakat Cirebon‖. Humaniora, vol. 25, no. 3,
2013, h. 281-285. 69
Setiono, Tionghoa dalam Pusaran Politik, (Jakarta: Elkasa, 2002), h. 18. 70
Diambil dari: https://www.radarcirebon.com/2018/03/23/cirebon-tionghoa-
perkawinan-budaya-yang-melekat/ . (Diakses pada 30 November, 2020).
130
melakukan aktivitas budayanya, ada beberapa orang Tionghoa non Muslim dan
etnis Tionghoa Muslim yang masih ikut mengelola secara bersama-sama setiap
ritual keagamaan, begitu juga dalam menjalankan tradisi dan adat istiadat.71
Dalam konteks di atas, penulis melihat di satu sisi, meskipun sebagian
masyarakat sudah menjadi Muslim, namun di sisi lain, aktivitas keagamaan dan
budaya tersebut masih dipegang kuat oleh mereka. Di samping kondisi tersebut
sebagai bentuk penghormatan terhadap siapa leluhurnya sekaligus dijadikan sebagai
momen penting untuk tetap menjaga keharmonisan dan kerukunan bersaudara di
tengah karakter keluarga yang pada kenyataannya memiliki keyakinan yang
berbeda. Kenyataan tersebut juga menurut penulis memperlihatkan bahwa aktivitas
budaya dan ritual keagamaan bisa menjadi wadah interaksi sosial di antara
masyarakat yang menganut agama berbeda, juga etnis. Mereka bersikap saling
menghormati dan mendukung dalam melakukan tradisi yang terdapat persamaan
nilai-nilainya. Aktivitas budaya tersebut dapat ditemukan di Cirebon, baik dalam
tradisi orang Tionghoa seperti perayaan Imlek, Barongsai, Ceng Beng,72
maupun
sebaliknya yakni pada saat masyarakat Tionghoa Muslim merayakan Idul Fitri,
ziarah kubur dan sebagainya.
Perlu digarisbawahi, meskipun etnis Tionghoa dianggap sebagi warga
pendatang tetapi etnis Tionghoa lebih berhasil dalam bidang ekonomi dibanding
masyarakat pribumi pada umumnya. Dalam konteks Cirebon, keberhasilan
Tionghoa dalam bidang ekonomi turut memengaruhi stabilitas perdagangan maupun
ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah setempat.73
Di samping Cirebon juga
masuk dalam salah satu tujuan pariwisata lokal maupun manca negara karena
daerah ini menyimpan segenap peninggalan historis masa silam seperti Istana
Kasepuhan dan Kanoman, makam Sunan Gunung Jati, Gua Sunyaragi, serta warisan
karya batik yang megah seperti batik khas Cirebon yang memiliki motif Mega
Mendung dan sebagainya. Sebagian dari apa yang disebutkan adalah merupakan
hasil atau produk dari perpaduan budaya etnis Tionghoa dan Cirebon di masa silam,
juga mengandung unsur-unsur dan nilai-nilai Islam,74
yang kemudian menarik
tujuan wisatawan dan peziarah saat ini. Dengan demikian hal tersebut ikut
memengaruhi kehidupan masyarakat Cirebon dalam aspek ekonomi, juga menjadi
71
P. S. Sopiah, ―Inpres No 14 Tahun 1967 dan Implikasinya Terhadap Identitas Muslim
Tionghoa Cirebon‖. Tamaddun, vol. 5, no. 2, 2017, h. 152-173. 72
Ceng BengGrave-sweeping day adalah tradisi/festival bagi etnis Tionghoa sebagai
bentuk penghormatan kepada leluhur mereka dengan mengunjungi makam atau kuburan
untuk berdoa yang dalam Islam dikenal dengan ziarah kubur. Lihat W. W. Hew,
―Negotiating ethnicity and religiosity: Chinese Muslim identities in post-new order
Indonesia‖, (A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy Department of
Political and Social Change School of International, Political and Strategic Studies College
of Asia and the Pacific of The Australian National University, 2011), h. 9 & 205. 73
A. Jaelani, ―Cirebon as the Silk Road: A New Approach of Heritage Tourisme and
Creative Economy‖. Journal of Economics and Political Economy (JEPE), vol. 3, no. 2,
2016, h. 264-283. 74
Hassan, ―Islamic tourism: The Concept and the Reality‖. Islamic Tourism, vol. 14,
no. 2, 2004, h. 35-45.; W. Ritter, ―Recreation and tourism in the Islamic countries‖. Ekistics,
1975, h. 56-59.
131
salah satu sumber pendapatan bagi daerah Cirebon sebagai akibat dari banyaknya
para wisatawan yang masuk di daerah ini.
Sebagai salah satu daerah di pantai utara Jawa, Cirebon termasuk daerah yang
berkembang pesat dalam perkembangan Islam. Ini didukung pula oleh pelabuhan
menjadi pertemuan strategis para pedagang dan komunitas lain dengan tujuan
berbeda. Secara ekonomi, Cirebon adalah pusat kota sekaligus kerajaan maritim
agraria yang lebih fokus pada kehidupan ekonomi perdagangan dan pertanian.
Adapun pertumbuhan dan perkembangan kota-kota kerajaan karena beberapa faktor
di antaranya faktor geografis, ekonomi, politik, kosmologi dan magis-religius.75
Penulis melihat sebagaimana pandangan umum penduduk pribumi, khususnya
bagi masyarakat Cirebon bahwa model awal yang telah melekat dari sifat etnis
Tionghoa yaitu rajin, ulet, hemat dan dapat dipercaya di dalam berdagang. Sehingga
tidak heran jika sebagian besar di antara mereka adalah termasuk kelompok
Hokkian. Usaha-usaha tersebut dapat dijumpai di pusat-pusat perdagangan dan
perbelanjaan di daerah Cirebon. Secara umum jenis pencaharian atau pekerjaan
yang ditekuni etnis Tionghoa baik Muslim maupun non Muslim adalah pedagang
dan pengusaha. Dengan demikian, hal tersebut juga memperlihatkan kepada kita
bahwa meskipun sebagian dari etnis Tionghoa telah memeluk Islam sebagai agama
yang diyakini, tetapi mereka tetap mengakui ajaran Tri Dharma yang telah
memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan etnis
Tionghoa, khususnya yang ada di Cirebon. Misalnya, sifat dapat dipercaya
membuat keberadaan mereka dalam persaingan ekonomi, khususnya perdagangan
selalu maju dan berkembang.
Cirebon, sebagai wilayah yang dihuni oleh komunitas budaya Cirebon,
memiliki karakteristik unik karena akulturasi antara Hindu, Hindu-Islam, etnis
Jawa-Sunda, etnis Arab- Tionghoa, kerajaan Mataram-Galuh Pakuan/Padjajaran,
dan Jawa Barat/Jawa Tengah. Selain itu, Cirebon juga merupakan wilayah lintas
antar pesisir daerah dan daerah pegunungan/dataran tinggi. Sehingga itu, perlu juga
untuk dikemukakan situasi linguistik di Cirebon dalam hal berkomunikasi. Di
Cirebon, sejumlah bahasa digunakan, yaitu bahasa Cirebon, bahasa Sunda Cirebon,
bahasa Indonesia, dan bahasa asing seperti bahasa Arab, Belanda dan Inggris, serta
bahasa Hokkien atau Hokkian.76
Bahasa Hokkian adalah salah satu bahasa yang
digunakan secara produktif oleh etnis Tionghoa di Losari, Cirebon (perbatasan
antara Jawa Barat dan Jawa Tengah). Akulturasi bahasa dan budaya antara
kelompok etnis Tionghoa dan kelompok asli dapat dilihat dari difusi yang jelas
dalam cara berpikir dan perilaku kedua kelompok etnis di wilayah tersebut.
Penelitian Darheni mengatakan primordialisme antara kelompok etnis asli dan
Tionghoa tidak terlihat jelas, yang menunjukkan pembentukan komunikasi dalam
75
M. D. Pusponegoro dan N. Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1991). 76
Bahasa Hokkien atau Hokkian (sederhana: 闽南语, tradisional: 閩南語) adalah salah
satu dari cabang bahasa Minnan (Min Selatan) yang merupakan bagian dari bahasa Han
(Tionghoa). Bahasa Hokkien juga dikenal sebagai bahasa Holo di daratan Tiongkok dan
Taiwan.
132
aspek sosial, ekonomi, pemerintahan, dan kekuasaan.77
Dengan demikian, bahasa
dan budaya Jawa (bahasa Cirebon-Jawa) adalah bagian dari budaya Indonesia
(termasuk dalam kategori bahasa Melayu), dan juga membuat kontribusinya sendiri
terhadap pengembangan adat, upaya untuk memelihara dan meningkatkan nilai
kemanusiaan, dan menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Menurut Ayatrohaedi bahasa yang digunakan oleh masyarakat adalah bahasa
Jawa dengan dialek Cirebon, bahasa Cirebon, bahasa Indonesia (sebanyak yang
dibutuhkan), dan bahasa lain seperti bahasa Arab, Tionghoa, dan Bugis. Misalnya,
di wilayah Cirebon, baik kota maupun pedesaan, ada daerah dengan penutur bahasa
Cirebon-Sunda.78
Sementara Darheni yang melakukan penelitian tentang penggunaa
bahasa di Losari, Cirebon mengatakan penggunaan bahasa di Losari, Cirebon
memiliki karakteristik yang unik, variasi bahasa Cirebon telah dicampur dengan
bahasa Hokkian. Ia menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa
lokalbahasa Cirebon-Jawa di Losari sangat memengaruhi perkembangan
linguistik di daerah itu, sehingga penutur bahasa Hokkian setempat memiliki
karakteristik bahasa mereka sendiri. Sementara itu, kosa kata bahasa Hokkian
memengaruhi perkembangan bahasa lokal, tetapi ini terbatas pada salam/panggilan
dan angka.79
Setiap kelompok atau masyarakat suku bangsa yang tinggal dan menetap di
lingkunggan tertentu memiliki kebudayaannya masing-masing dengan simbol-
simbol yang mungkin hanya bisa dimengerti secara tepat oleh masyarakat dalam
lingkungannya sendiri, karena pada dasarnya kebudayaan merupakan respon
manusia terhadap lingkungan dan persoalan yang dihadapi. Dengan demikian setiap
etnis pasti memiliki budaya masing-masing yang mungkin berbeda atau sama
dengan etnis lainnya. Misalnya suku Minang80
dan suku Sunda81
yang mayoritas
Islam atau suku Minahasa82
dan suku Batak,83
sekalipun memiliki agama dan
77
N. Darheni, ―The Language Characteristic and Its Acculturation from Chinese
Speakers in Losari, Cirebon Regency, West Java: The Acculturation of Chinese with
Javanese Culture‖. KnE Social Sciences, 2018, h. 663-686. 78
Ayatrohaedi, Dialektologi sebuah pengantar (An introduction to dialectology),
(Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979). 79
Darheni, ―The Language Characteristic…, h. 663-686. 80
L. K. Alfirdaus, E. Hiariej, & F. Adeney-Risakotta, ―The Position of Minang-Chinese
Relationship in the History of Inter-ethnic Groups Relations in Padang, West
Sumatra‖. Jurnal Humaniora, vol. 28, no. 1, 2016, h. 79-96.; A. Widyanti, L. Susanti, I. Z.
Sutalaksana, & K. Muslim, ―Ethnic differences in Indonesian Anthropometry Data:
Evidence from Three Different Largest Ethnics‖. International Journal of Industrial
Ergonomics, vol. 47, 2015, h. 72-78. 81
D. S. Anshori, ―The Construction of Sundanese Culture in the News Discourse
Published by Local Mass Media of West Java‖. Lingua Cultura, vol. 12, no. 1, 2018, h. 31-
38.; A. Hasanah, N. Gustini, & D. Rohaniawati, ―Cultivating Character Education Based on
Sundanese Culture Local Wisdom‖. Jurnal Pendidikan Islam, vol. 2, no. 2, 2016, h. 231-
253. 82
E. Lobja, A. Umaternate, T. Pangalila, H. Karwur, & Y. Burdam, ―The
Reconstruction of Cultural Values and Local Wisdom of the Tombulu Sub-Ethnic of
Minahasa Community in the Walian Village of Tomohon City‖. In International Conference
133
kepercayaan yang sama, namun kenyataannya masing-masing di antara mereka
memiliki tradisi dan tata cara pelaksanaannya yang berbeda. Hal tersebut terjadi
karena adanya pengaruh dari kearifan lokal (local wisdom)84
masing-masing suku.
Selain beberapa suku yang disebutkan di atas, hal yang sama juga terjadi pada
masyarakat Cirebon. Tradisi-tradisi yang berkembang di dalam keraton Cirebon
adalah merupakan warisan budaya yang berlangsung turun temurun dari para
pendahulu keraton,85
yaitu dari Pangeran Cakrabuana,86
Sunan Gunung Jati terus
kepada keturunannya. Kesultanan Cirebon menjadi sebuah kerajaan yang berdaulat
adalah pada masa Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memutuskan untuk tidak
lagi mengirimkan upeti kepada Prabu Siliwangi yang notabene juga adalah
kakeknya. Setidaknya ada dua peran yang melekat pada sosok Sunan Gunung Jati,
yakni selain sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Kesultanan Cirebon, ia juga
merupakan seorang Waliyullah. Sehingga wajar jika terjadi dialektika yang terus-
menerus antara institusi keagamaan dan simbol kekuasaan. Dialektika itu terlihat
dengan banyak digunakannya simbol Islam dalam upacara atau tradisi kekratonan
dan dalam kehidupan masyarakat Cirebon seperti upacara Mauludan berdialektika
dengan tradisi Islam yang dikenal sampai sekarang dengan pembacaan Barzanji,
marhaban dan sholawat. Dengan demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa perjumpaan
Islam dan budaya dengan komunitas masyarakat Cirebon telah melahirkan budaya
masyarakat Cirebon yang religius, tetapi khas dan unik sebagai wujud harmoni dari
ritus keagamaan yang berasal dari nilai-nilai Islam dan tradisi setempat.87
Beberapa kajian ilmiah tentang kehidupan orang-orang Tionghoa telah
dilakukan. Pada umumnya, kajian-kajian tersebut lebih menekankan pada aspek
on Social Science 2019 (ICSS 2019), (Atlantis Press, 2019).; N. Kaliki, ―The Symbol of
Traditional Cloths of Kabasaran Dance‖. Linguistic Journal, vol. 6, no. 1, 2018, h. 30-40. 83
H. P. Manalu, ―Adat Batak Ditinjau dari Perspektif Iman Kristen‖. Haggadah, vol. 1,
no. 1, 2020, h. 32-41. 84
H. Habibi, ―Protecting National Identity Based on the Value of Nation Local
Wisdom‖. International Journal of Malay-Nusantara Studies, vol. 1, no. 2, 2018, h. 24-40.;
R. Sinaga, F. Tanjung, & Y. Nasution, ―Local Wisdom and National Integration in
Indonesia: A Case Study of Inter-Religious Harmony amid Social and Political Upheaval in
Bunga Bondar, South Tapanuli‖. Journal of Maritime Studies and National Integration, vol.
3, no. 1, 2019, h. 30-35. 85
―Java, Boordevol Cultuur‖, dalam Algemeen Dagblad, Rotterdam, 18-05-1993, h.
25. 86
Selain tradisi-tradisi di dalam keraton, transformasi sosial dan politik dari Hinduisme
Pajajaran menjadi Cirebon Islam telah dimulai setelah Pangeran Cakrabumi (juga dikenal
sebagai Pangeran Cakrabuana) mendeklarasikan kemerdekaan Cirebon dari Pajajaran. Ia
tidak hanya mendirikan pusat pemerintahan yang independen di Pakungwati, tetapi juga
secara aktif menyebarkan ajaran Islam di tanah Cirebon. Salah satu warisannya adalah
mesjid kecil yang disebut ―Tajug Jalagrahan‖. Lihat D. Hamdani, ―Cultural System of
Cirebonese People: Tradition of Muludan in the Kanoman Kraton Indonesian‖. Journal of
Social Sciences, vol. 4, no. 1, 2012 11-22.; D. Wildan, Sunan Gunung Jati: Pembumian
Islam dengan Pendekatan Struktural dan Kultural (Antara Fiksi dan Fakta), (Bandung,
Humaniora Utama Press, 2002), h. 272-273. 87
A. Yani, ―Pengaruh Islam Terhadap Makna Simbolik Budaya Keraton-Keraton
Cirebon‖. Holistik, vol. 12, no. 01, 2011, h. 181-196.
134
ekonomi dan politik. Gambaran serupa dapat ditemukan pada Babat Tanah Jawi
atau Babat Melayu. Meski demikian, kajian-kajian ilmiah tersebut kurang menaruh
perhatian pada aspek budaya etnis Tionghoa dalam konteks Cirebon yang pada
sebenarnya memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Bukti
arkeologis dan antroplogis menunjukkan bahwa kontak budaya antara etnis
Tionghoa, atau Tionghoa dengan penduduk Nusantara atau Indonesia saat ini sudah
berlangsung berabad-abad. Beberapa bukti tersebut tampak dari ukiran padas dalam
arsitektur keraton dan Taman Air Sunyaragi (Guha Sunyaragi) di Cirebon; ukiran
cadas di masjid kuno Mantingan, Jepara;88
menara masjid di Pecinan Banten;89
konstruksi pintu makam Sunan Giri di Gresik;90
konstruksi masjid Demak (soko
tatal dan lambang kura-kura);91
atau kaitan masjid Kali Angke dengan Gouw Tjay
dan masjid Kebun Jeruk yang didirikan oleh Tamien Dosol Seeng dan Nyonya
Cai.92
Dalam banyak segi, fakta ini menunjukkan posisi sosial Tionghoa Muslim
dalam struktur komunitas Muslim Indonesia.93
Beberapa di antara mereka
menempati posisi sehingga memainkan peran yang strategis dalam pengembangan
syiar dan perkembangan Islam di Nusantara, Indonesia saat in, termasuk Cirebon.
Internalisasi ajaran Islam awal yang dilakukan oleh Tionghoa Muslim tidak
dapat ditentukan secara pasti. Tetapi paling tidak, secara umum dapat dikatakan
bahwa proses tersebut telah berlangsung sejak pertama kali mereka datang ke
Indonesia. Karena alasan sosial budaya, keberagamaan Tionghoa Muslim erat
dengan konteks sosial ekonomi mereka, khususnya sebagai pedagang di perkotaan.
Berbeda dengan keberagamaan etnis lain sebagaimana dari Gujarat, jika yang
terakhir melakukan mobilitas hingga ke pedalaman, maka Tionghoa Muslim
cenderung mengembangkan kehidupan keagamaan mereka di pesisir,94
yang pada
waktu itu merupakan pusat perkotaan Muslim.
88
S. Al Qurtuby, ―The Imprint of Zheng He and Chinese Muslims in Indonesia‘s
Past‖. Zheng He and the Afro-Asian World, Chapter 8, h. 171-186.; F. B. Buseri, ―The Role
of Chinese Ethnic in Spread of Islam in Indonesia‖. In Proceeding of The International
Seminar and Conference on Global Issues, vol. 1, no. 1, 2015, h. 48-54. 89
T. E. Darmayanti & A. Bahauddin, ―The Influence of Foreign and Local Cultures on
Traditional Mosques in Indonesia‖. In Islamic Perspectives Relating to Business, Arts,
Culture and Communication, (Singapore: Springer, 2015), h. 175-183. 90
A. Muzzaki, ―Cheng Hoo Mosque: Assimilating Chinese Culture, Distancing it from
the State‖. CRISE: Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity
Working Paper, no. 70, 2010, h. 1-29. 91
B. Wiryomartono, ―Patrimonial Figure and Historic Sites in Banda Aceh and
Demak‖. In Traditions and Transformations of Habitation in Indonesia, (Singapore:
Springer, 2020), h. 265-282.; M. N. Rokhman & L. Yuliana, ―History Learning at Secondary
School about Demak Kingdom‖. Journal of Social Studies (JSS), vol. 14, no. 1, 2018. 92
D. Lombard & C. Salmon, ―Islam and Chineseness‖. Indonesia, no. 57, 1993, h. 115-
131. 93
W. Zhuang, ―Photography and Chineseness: Reflections on Chinese Muslims in
Indonesia‖. Inter-Asia Cultural Studies, vol. 20, no. 1, 2019, h. 107-130.; S. Y. Chiou,
―Search of New Social and Spiritual Space: Heritage, Conversion, and Identity of Chinese-
Indonesian Muslims‖, (Doctoral Dissertation, Utrecht University, 2012). 94
Y. Z. Abidin, ―Keberagamaan dan Dakwah Tionghoa Muslim‖. Ilmu Dakwah:
Academic Journal for Homiletic Studies, vol. 11, no. 2, 2017, h. 357-368.
135
Cirebon sebagai garis sutra menjadi pusat pelabuhan yang sibuk serta pusat
tamaddun Islam yang memiliki beberapa karakter, antara lain, yaitu: pertama,
pertumbuhan Islam menghembuskan kehidupan kota dengan pola masyarakat dan
persiapan hirarki sosial yang kompleks. Kedua, perkembangan arsitektur baik sakral
dan profan, misalnya, Masjid Agung Cirebon, istana Kasepuhan, Kanoman,
Kacerbonan dan Kaprabonan, bangunan Siti Inggil mengadaptasi desain dan
ornamen lokal termasuk Tionghoa dan Islam. Ketiga, tumbuhnya seni lukis kaca
dan patung yang menghasilkan karya-karya kaligrafi Islam sangat khas Cirebon,
yang antara lain juga menunjukkan adanya unsur-unsur antropomorfik yang tidak
lazim dalam seni Islam. Keempat, tumbuhnya dan perkembangan seni seperti tari,
batik, musik dan berbagai seni pertunjukan tradisional bernafaskan Islam, ornamen
khas awan Cirebon, dan lainnya. Kelima, Cirebon masuk ke jaringan penyiaran
Islamis yang dipimpin oleh Wali Songo yang terkenal di pulau Jawa. Keenam,
tumbuhnya penulisan teks-teks agama dan pemikiran keagamaan bahwa fisik tetap
tersimpan di istana dan tempat lain di Jawa Barat, yang masih membutuhkan
peninjauan mendalam. Ketujuh, tumbuhnya proliferasi jemaah syariah di Cirebon
yang kemudian melahirkan karya sastra berupa mistik berserat yang mengandung
ajaran tujuh wujudiyah atau martabat. Tradisi serat mistisisme kemudian sangat
berpengaruh pada penulisan tradisi sastra. Delapan, berkembangnya institusi
pendidikan Islam dalam bentuk sekolah agama di Cirebon, Indramayu, Karawang,
Majalengka dan Kuningan.95
Agama Islam masuk ke Cirebon pada permulaan abad ke-15 bersamaan dengan
terjadinya kontak pertama antara orang-orang Arab dan Tionghoa dengan pribumi.
Islam pun dikenal oleh masyarakat Cirebon sebagai agama pendatang yang dibawa
oleh para pedagang Arab dan Tionghoa. Namun, karena saat itu belum terjadi
kontak budaya yang signifikan, penyebaran Islam pun baru terjadi secara masif
pada masa Sunan Gunung Jati berkuasa di Cirebon. Ketika pertama datang orang-
orang Arab dan Tionghoa menempati wilayah pesisir Cirebon. Sebagai pedagang,
mereka lebih banyak melakukan aktivitasnya di sana, maka tidak heran jika hanya
wilayah pesisir saja yang sejak awal telah mengenal Islam.
Secara historis Hubungan orang-orang Tionghoa dengan masyarakat Cirebon
dimulai sejak kedatangan Cheng Ho dan pasukannya yang berjumlah kurang lebih
27.000 orang di Pelabuhan Muara Jati pada tahun 1415 M. Menurut Ibnu Bathutah,
di setiap Pelabuhan dan tempat yang disinggahi Cheng Ho selalu menempatkan
perwakilan dagang, konsul politik dan Gudang-gudang Tiongkok. Namun karena
saat itu belum berdiri kerajaan Cirebon dan Pelabuhan Muara Jati hanya sebuah
Pelabuhan kecil, Cheng Ho hanya menempatkan orang-orangnya yang mau tinggal
di Cirebon. Dalam buku ―Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI, De Graaf
menceritakan bahwa Haji Kung Wu Ping yang merupakan anak buah Cheng Ho
membangun komunitas Tionghoa muslim Hanafi di Sembung, Sarindil dan Talang.
Kemudian Haji Tan Eng Hoat alias Maulana Ifdhil Hanafi alias Pangeran Adipati
95
A. B. Lapian & E. Sedyawati, ―Kajian Cirebon dalam Kajian Jalur Sutra‖. Cirebon
sebagai Bandar Jalur Sutra (Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah), (Jakarta: Departemen
Pendidikandan Kebudayaan RI, 1997).
136
Wirasanjaya mengembangkan pemukiman Tionghoa muslim.96
Haji Tan Eng Hoat
membantu Sunan Gunug Jati menyebarkan dan mengembangkan Islam ke Priangan
Timur sampai ke Garut juga ikut membantu Sunan Gunung Jati melawan kerajaan
Galuh. Maulana Ifdhil Hanafi alias Haji Tan Eng Hoat menjadi raja muda bawahan
Kesultanan Cirebon dan berkedudukan di Kadipaten. Ponakannya yang bernama
Tan Sam Cai alias Muhammad Syafei alias Tumenggung Aria Dwipa Cula juga
punya peran penting dalam Kesultanan Cirebon. Tan Sam Cai pernah menjabat
sebagai bendahara kerajaan, bahkan ada juga yang mengatakan dia merupakan
arsitektur Guha Sunyaragi. Tan Sam Cai digambarkan sebagai administrator yang
baik. Tan Sam Cai sangat berjasa dalam memperkuat Kesultanan Cirebon dengan
keuangannya. Juru kunci makam keluarga Kesultanan di Sembung juga dipegang
oleh Haji Kung Sem Pak alias Haji Nurjani.97
Para pedagang asing itu banyak berinteraksi dengan penduduk lokal.
Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk menetap di Cirebon.
Mereka kemudian menikahi perempuan-perempuan pribumi. Beberapa orang
Tionghoa berperan penting di Kesultanan Cirebon pada periode awal. Keberadaan
mereka berdampak pada perkembangan kebudayaan di masyarakat sebagaimana
terlihat pada bangunan, kesenian, hingga benda-benda pusaka. Pengaruh tradisi
Tionghoa pun cukup kental terasa di Cirebon. Beberapa masjid kuno di sana
menggunakan keramik dari Tiongkok untuk hiasan dindingnya. Jumlahnya tidak
sedikit dan motifnya pun sangat beragam.
Keramik-keramik itu didatangkan langsung dari Tiongkok. Sebagian besar
dibawa oleh para pedagang, sementara sisanya didapat dari utusan raja. Namun, ada
juga yang dibuat oleh etnis Tionghoa yang sudah menetap di Cirebon. Tidak hanya
di masjid, keramik-keramik Tiongkok juga menghiasi bangunan publik lainnya,
bahkan di makam Sunan Gunung Jati pun tersebar hiasan-hiasan keramik Tiongkok.
Hal itu diperkuat dengan keberadaan istri Sunan Gunung Jati yang berdarah
Tionghoa, yakni Ong Tien Nio. Selain itu, nuansa Tionghoa juga terlihat pada salah
satu motif batik Cirebon, yakni mega mendung. Sementara Hardjasaputra menyebut
bahwa gambaran naga pada kereta pusaka Kesultanan Cirebon sangat erat kaitannya
dengan kebudayaan Tionghoa. Namun, Hardjasaputra mengatakan selain menyerap
budaya luar yang bersifat positif, diduga sebagian warga masyarakat Cirebon juga
menyerap budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam, salah satunya adalah
arak.98
Pendapat Hardjasaputra didasarkan pada keberadaan pabrik arak di Cirebon
yang dikelola oleh etnis Tionghoa. Dalam ―Eenige Offciele Stukken met Betrekking
tot Tjirebon‖, laporan resmi pemerintah Belanda yang ditulis Brandes menyebut
96
H.J. de Graaf dkk, Cina Muslim di Jawa Abad XV Dan XVI: Antara Historisitas dan Mitos,(Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 19..),h. 34-36. 97
97
H.J. de Graaf dkk, Cina Muslim di Jawa…, h. 42-44. 98
A. S. Hardjasaputra, Cirebon dalam Lima Zaman: Abad ke-15 hingga
Pertengahan Abad ke-20, (Bandung: Penerbit Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa
Barat, 2011).
137
kebiasaan minum minuman keras telah menjadi budaya di pelabuhan-pelabuhan
Cirebon yang dibawa oleh para pedagang dari mancanegara.99
Setidaknya ada tiga tahapan kedatangan etnis Tionghoa di Cirebon yang
dimulai dari tahun yang paling awal, yaitu: Pertama, sekitar tahun 1415 M, dengan
adanya rombongan Laksamana Ceng Ho yang datang ke Cirebon bersama armada
angkatan lautnya dengan membawa 63 Perahu yang memuat 27.800 orang yang
terdiri dari perwira, prajurit, tabib, para ahli perbintangan, dan para penerjemah.100
Kedatangan Laksamana Ceng Ho mungkin juga meninggalkan masyarakat
Tionghoa pertama di Cirebon. Menurut Huang dalam bukunya Budaya Etnis
Tionghoa Cirebon mengatakan bahwa ketika Laksamana Ceng Ho beserta
rombongannya termasuk Ma Huan, dalam perjalannanya ke Majapahit dan mampir
ke Cirebon selama 7 hari 7 malam mereka meninggalkan beberapa rombongannya
di daerah ini, bahkan dikatakan juga, Ma Huan telah menikahi seorang wanita yang
masih punya tali persaudaraan dengan Ki Gedeng Tapa (Penguasa Pelabuhan
Cirebon) yang bernama Nyai Rara Rudra.101
Kedua, sekitar akhir abad 15, Cirebon didatangi oleh Putri Ong Tien yang
memiliki tujuan untuk mencari Sunan Gunung dan menikahinya.102
Tujuan Putri
Ong Tien mencari Sunan Gunung Jati karena untuk menyembuhkan perutnya yang
kelihatan hamil. Yang awal ceritanya ketika itu sunan Gunung Jati pergi ke negeri
Tiongkok untuk berdakwah. Di sana Sunan Gunung Jati terkenal sakti dan kerap
menyembuhkan orang sakit yang pada akhirnya Raja Tiongkok mencoba kesaktian
Sunan Gunung Jati dengan cara menebak isi perut putrinya yang ketika itu terlihat
membuncit karena adanya buntelan kain yang sengaja di pasang oleh putri itu
dengan perintah raja. Ketika Sunan Gunung Jati menjawab bahwa perut itu
membuncit karena hamil, Raja Tiongkok itu langsung ketawa dan langsung
memerintahkan Sunan Gunung Jati pergi dari negeri Tiongkok. Pasca Sunan
Gunung Jati pergi, ternyata Putri Tiongkok menjadi benar-benar hamil. Raja
Tiongkok pun langsung menyuruh prajuritnya untuk menyusul Sunan Gunung yang
telah diusirnya, Sunan Gunung Jati tidak bisa ditemukan karena mungkin sudah
pergi dari negara Tiongkok yang pada akhirnya putri tersebut mencari sendiri
sampai ke daerah Cirebon.103
Ketiga, pada abad 18-an saat banyak pelarian etnis
Tionghoa dari wilayah Batavia yang datang ke wilayah Cirebon. Hadinoto dalam
karya Mahdun menyebut bahwa etnis Tionghoa yang ada di Cirebon sudah ada
sebelum bangsa Eropa masuk dalam wilayah tersebut. Dibuktikan dengan adanya
99
J. L. A. Brandes, ―Eenige Officiele Stukken met Betrekking tot Tjirebon‖. TBG, vol.
37, 1894, h. 449-488. 100
D. K. Laksmiwati, Putri Ong Tin Mengarungi Samudra Asmara Merahi Cinta Sejati
Sesuhunan Jati Romantika Caruban Nagari, ed. 1, cet. 2, (Yogyakarta: Deepublish, 2014),
h. 12. 101
Huang, Budaya Etnis Tionghoa…, h. 18. 102
Raden S. Hidayat, Sejarah Caruban Kawedar, (Cirebon: Badan Komunikasi
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, 2008), h. 65. 103
Hidayat, Sejarah Caruban Kawedar, h. 66.
138
pemukiman orang Tionghoa sebelum benteng ―de Bescherming‖ milik VOC yang
didirikan di Kota Cirebon.104
Berdasarkan pemaparan di atas, pergumulan budaya etnis Tionghoa dan
masyarakat Cirebon di Kesultanan Cirebon telah menghasilkan akulturasi budaya
yang bisa ditemukan di Keraton Kasepuhan dan artefak-artefak bersejarah lainnya.
Penulis menemukan bahwa bangunan bersejarah seperti Keraton Kasepuhan dan
berbagai artefak memiliki keistimewaan tersendiri, unik dan karakteristiknya
berbeda dengan keraton-keraton maupun artefak-artefak lainnya. Keraton
Kasepuhan dan beberapa peninggalannya begitu kental dengan ornamen dari luar,
terutama ornamen-ornamen Tionghoa. Ornamen Tionghoa yang begitu kuat tidak
dapat dilepaskan dari peran etnis Tionghoa yang hadir, utamanya putri Tiongkok
bernama Ong Tien Nio, yang tidak hanya fisik tetapi juga jiwanya. Ong Tien Nio
adalah sosok yang sangat berarti bagi sang penguasa Sunan Gunung Jati sebab ia
adalah salah satu istrinya. Lebih jauh penulis ingin mengatakan bahwa jika tidak
ada fisik dari Tiongkok yang hadir di Kesultanan Cirebon ketika itu, maka tidak
mungkin ruangan sultan yang begitu private seperti Astana Gunung Jati, Kereta
Kencana Singa Barong, masjid Astana Gunung Jati, Guha Sunyaragi, Batik Mega
Mendung, dan sebagainya dipenuhi ornamen-ornamen Tionghoa. Semua itu
menjadi bukti betapa berperannya seorang perempuan dalam ruang dan makna,
sehingga turut mewarnai suasana di dalam Kesultanan Cirebon.
Sebagai seorang putri Tiongkok, Ong Tien Nio sebagaimana di atas otomatis
hadir dengan filosofi agamanya yaitu Tao dengan konsep Yin Yang (keseimbangan).
Keseimbangan dalam konteks penelitian ini dimaknai bahwa raja dan ratu itu tidak
berhadapan, juga tidak atas dan bawah tetapi saling melengkapi laksana orang yang
berangkulan. Merujuk dalam falsafah Tiongkok, simbol Yin dan Yang mengandung
beberapa makna dan tafsiran, yakni dalam Yin terdapat Yang (dalam gelap ada
terang), begitu juga sebaliknya. Yin dan Yang merupakan lambang ajaran falsafah
Taoisme.105
Konsep Yin Yang menggambarkan bahwa segala sesuatu dalam alam
semesta mempunyai aspek yang berlawanan: ada putih dan ada yang hitam; ada
baik dan buruk; sejuk dan panas; siang dan malam; musim kemarau dan musim
hujan; surga dan neraka. Lebih jauh, konsep Yin Yang digunakan untuk
menggambarkan bahwa sesuatu yang saling bertentangan dan saling bergantung itu
sebuah keniscayaan.106
Yin dan Yang digambarkan seperti telur, yang bagian kuning
dan putihnya terpisah. Yang melambangkan surga, laki-laki, matahari, terang,
104
Hadinoto, ―Lingkungan Pecinan dalam Tata Ruang Kota di Jawa Pada Masa
Kolonial‖, dalam Mahdun, ―Konflik Cina-Pribumi dan Dampaknya Bagi Pertumbuhan
Industri Batik di Trusmi 1948‖. Jurnal Tamaddun, vol. 5, no. 2, 2017, h. 76-93. 105
Tony Fang, ―Yin Yang: A new perspective on culture‖. Management and
organization Review, vol. 8, no. 1, 2012, h. 25-50.; Xinyan Jiang, ―Chinese dialectical
thinking—the yin yang model‖. Philosophy Compass, vol. 8, no. 5, 2013, h. 438-446. 106
Mondo Secter, ―The yin-yang system of ancient china: The yijing-book of changes
as a pragmatic metaphor for change theory‖. Journal for Interdisciplinary and Cross-
Cultural Studies, vol. 1, no. 1, 1998, h. 85-106.; Stefan Jaeger, ―A geomedical approach to
chinese medicine: the origin of the Yin-Yang symbol‖. Recent Advances in Theories and
Practice of Chinese Medicine, 2012, h. 29-44.
139
kekuatan, dan hal positif lainnya. Sementara Yin melambangkan tanah, bulan,
kegelapan, wanita, dingin, lembut, mati, angka ganjil, dan sesuatu yang negatif.
Konsep Yin Yang walaupun bertentangan antara satu sama lain, namun
keduanya bersikap saling melengkapi seperti laki-laki dan perempuan, meskipun
berbeda, namun perlu bersama-sama untuk mewujudkan generasi baru. Konsep Yin
Yang juga diterangkan dalam al-Qur‘an surat Yasin [36] ayat 36-37. Ayat ini
menjelaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan segala sesuatu secara tawazun
atau seimbang, yaitu dengan diciptakannya setiap sesuatu secara berpasangan.
Dalam konteks ini, tawazun (seimbang) dalam Islam sejalan dengan konsep Yin
Yang dalam falsafah Tiongkok, yang juga menekankan pada keseimbangan.
Sehingga menurut penulis, konsep Yin Yang juga sejalan dengan nilai-nilai Islam,
dimana Islam sebagai sebuah agama mengajarkan pemeluknya untuk senantiasa
bersikap seimbang dalam berbagai aspek kehidupan. Dunia-akhirat adalah
seimbang, kita tidak bisa mengabaikan urusan akhirat hanya untuk urusan dunia,
begitupun sebaliknya.
141
BAB V
BUDAYA TIONGHOA DAN CIREBON DI KESULTANAN CIREBON:
MAKNA SIMBOLIK DAN FILOSOFIS
Mengacu pada pendapat Koentjaraningrat yang membagi wujud kebudayaan
menjadi tiga, maka pada bab inti ini penulis akan focus pada kebudayaan fisik yang
merupakan hasil ide atau pikiran-pikiran dan Tindakan manusia. Bagian ini adalah
lanjutan dari pembahasan sebelumnya, dan merupakan bab inti penelitian yang
menguraikan beberapa beberapa wujud budaya sebagai hasil akulturasi budaya
Tionghoa dan budaya Cirebon di Kesultanan Cirebon. Dari sejumlah wujud budaya
yang terakulturasi, penulis lebih banyak menghadirkan dan menganalisis wujud
budaya seperti yang terdapat dalam arsitektur bangunan Keraton Kasepuhanmulai
dari Gapura Siti Inggil, lima bangunan tanpa dinding dan beratap sirap (Mande
Malang Semirang, Mande Semar Tinandu, Mande Pandawa Lima, Mande
Pelinggihan/Pengiring, dan Mande Karesmen), Makam Astana Gunung Jati dan
Guha Sunyaragi/Taman Air Sunyaragi. Selain itu, diuraikan dan dianalisis pula
beberapa peninggalan seperti Kereta Kencana Singa Barong dan batik. Penulis
kemudian memunculkan makna-makna simbolik dan filosofis yang ada dibalik
semua wujud budaya tersebut, kemudian menganalisisnya menggunakan beberapa
teori akulturasi yang digagas oleh para sarjana dan pendukungnya, yang
mengatakan bahwa jika dua kelompok individu yang memiliki budaya berbeda
bersentuhan langsung atau bertemu, maka akan mengakibatkan perubahan dalam
pola budaya asli dari salah satu atau kedua kelompok tersebut. Namun tidak
kehilangan identitas atau karakteristik budaya masing-masing.1
Suatu budaya diciptakan selalu tanpa terlepas dari sebuah makna. Umumnya
makna budaya tersebut diciptakan dengan menggunakan simbol-simbol
sebagaimana juga simbol-simbol yang ada di Keraton Kasepuhan. Dilihat dari
pengertian simbol secara umum mencakup berbagai aspek yang luas. Namun yang
perlu diperhatikan adalah bahwa setiap daerah memiliki simbol budaya yang
berbeda-beda, yang membedakan ciri khas masing-masing. Berbicara mengenai
simbol, otomatis juga akan berbicara mengenai semiotika. Piliang mengatakan
semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda (sign), berfungsinya tanda, dan
produksi makna.2 Tanda dalam kehidupan manusia selalu menyampaikan suatu
informasi sehingga mempunyai sifat komunikatif. Mengutip teori Peirce dalam
Queiroz dan Stjernfelt bahwa tanda-tanda dalam gambar dapat digolongkan ke
1R. Redfield, R. Linton, & M. J. Herskovits, “Memorandum for the Study of
Acculturation”. American Anthropologist, vol. 38, no. 1, 1936, h. 149-152.; R. Thurnwald,
“The Psychology of Acculturation”. American Anthropologist, vol. 34, no. 4, 1932, h. 557-
569.; F. M. Keesing, Culture Change: An Analysis and Bibliography of Anthropological
Sources to 1952, no. 1. (New York: Octagon Books, 1973).; Koentjaraningrat, Beberapa
Pokok Antropologi Sosial, (Jakarta: Dian Rakyat, 1977), h. 142.; W. A. Haviland, Cultural
Anthropology, (Wadsworth Publishing Company, 2002).; J. W. Berry, “Globalisation and
Acculturation”. International Journal of Intercultural Relations, vol. 32, no. 4, 2008, h. 328-
336. 2Y. A. Piliang, “Semiotik Teks: Sebuah Pendekatan Analisis Teks”. Jurnal
Komunikasi, vol. 5, no. 2, 2004, h.189-198.
142
dalam ikon, indeks, dan simbol.3 Ikon adalah tanda yang mirip dengan objek yang
diwakilinya. Dapat pula dikatakan, ikon adalah tanda yang memiliki ciri-ciri yang
sama dengan apa yang dimaksudkan. Indeks merupakan tanda yang memilik
hubungan sebab-akibat dengan apa yang diwakilinya atau disebut juga tanda
sebagai bukti. Simbol merupakan tanda berdasarkan konvensi, peraturan, atau
perjanjian yang disepakati bersama. Simbol baru dapat dipahami jika seseorang
sudah mengerti arti yang telah disepakati sebelumnya. Pemahaman terhadap simbol
dapat diidentifikasi sebagai kata benda, kata kerja dan kata sifat. Simbol sebagai
kata benda dapat berupa barang, obyek, tindakan dan hal-hal kongkrit lain. Simbol
sebagai kata kerja dapat berfungsi sebagai menggambarkan, menyelubungi,
mengartikan, menunjukkan, memanipulasi, dan menandai. Simbol sebagai kata sifat
berarti sesuatu yang lebih besar, lebih bermakna, lebih bernilai, sebuah
kepercayaan, dan prestasi. Fungsi simbol digunakan untuk menjembatani obyek
atau hal-hal yang nyata dengan hal-hal yang abstrak yang maknanya melebihi dari
makna hal yang tampak. Mengacu pada teori simbol Elias, Bucholc mengatakan
simbol adalah kreasi manusia untuk mengejawantahkan ekspresi dan gejala-gejala
alam dengan bentuk-bentuk bermakna, yang artinya dapat dimengerti dan disepakati
oleh masyarakat tertentu.4 Adapun filsafat atau filosofis menurut KBBI adalah
pengetahuan dan penyelidikan mengenai hakikat segala sesuatu, sebab, asal dan
hukumnya dengan menggunakan akal pikiran. Jadi yang dimaksud makna filosofis
adalah sebuah usaha atau ikhtiar untuk mengungkap hakikat yang sebenarnya dari
suatu wujud budaya. Begitupun dengan budaya-budaya material yang ada di
Kesultanan Cirebon sebagai hasil akulturasi berbagai budaya tidak lepas dari makna
simbolik dan filosofis.
Berger dan Luckmann mengatakan simbol adalah usaha yang dilakukan oleh
manusia dalam melembagakan pandangan atau pengetahuan mereka tentang
masyarakat. Manusia membangun dunia simbolik yang universal yag dinamakan
pandangan hidup atau ideologi dengan memandang masyarakat sebagai proses yang
dinamis. Dengan demikian kenyataan sosial yang ada merupakan suatu konstruksi
sosial buatan masyarakat sendiri dalam perjalanan sejarahnya dari masa silam, ke
masa kini dan menuju masa yang akan datang.5 Sementara Turner mengatakan
bahwa dengan mengkaji simbol maka akan diketahui siapa pemilik kebudayaan dan
siapa pewarisnya di masa yang akan datang. Simbol merupakan sesuatu yang sangat
dikenal dan dipahami oleh masyarakat karena ia hadir dalam keseharian mereka.6
Dalam konteks penelitian ini, mempelajari dan memahami simbol dapat membawa
kita mengetahui kondisi sosial ketika sejumlah benda peninggalan atau wujud
3J. Queiroz & F. Stjernfelt, “Introduction: Peirce‟s Extended Theory and
Classifications of Signs”. Semiotica, vol. 2019, no. 228, 2019, h. 1-2. 4M. Bucholc, “Schengen and the Rosary” Historical Social Research/Historische
Sozialforschung, vol. 45, no. 171, 2020, h. 153-181. 5P. L. Berger dan T. Luckmann, Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang
Sosiologi Pengetahuan, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. XIII-XIV. 6V. Turner, “Symbolic Studies”. Annual Review of Anthropology, vol. 4, 1, 1975, h.
145-161. Lihat juga V. Turner, “Process, System, and Symbol: A New Anthropological
Synthesis”. Daedalus, 1977, h. 61-80.
143
budaya material yang ada di Keraton Kasepuhan itu dibentuk, bahkan keadaan
sosial sebelum benda-benda peninggalan itu digagas.
Sifat multikultural seni diharapkan dapat dijadikan dasar pemersatu bangsa
dengan mengembangkan kemampuan manusia untuk saling menghargai akan
adanya perbedaan. Pemahaman terhadap keanekaragaman budaya yang dimiliki
merupakan sebuah landasan yang kuat dalam mempersatukan perbedaan menjadi
kesatuan yang utuh. Akan tetapi, ketidakpahaman terhadap keanekaragaman yang
dimiliki merupakan akar perpecahan dan permusuhan. Dengan demikian, seni
dengan berbagai sifat yang ada memiliki arti dan peran penting dalam pendidikan.
Seni merupakan media dalam menanamkan nilai-nilai luhur yang terkandung misi
pendidikan. Seni juga merupakan sarana yang tepat dalam rangka transformasi ilmu
pengetahuan pada diri seseorang. Islam sebagai agama yang sarat dengan nilai-nilai
serta norma-norma yang mengikat di dalammya, memiliki aturan tersendiri bagi
umatnya yang apabila umat mau dan patuh melaksanakannya, maka ia akan
mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam upaya inilah seni diperlukan
dalam proses transformasi ilmu serta nilai-nilai luhur pendidikan Islam.7
A. Arsitektur Keraton Kesepuhan
Salah satu bagunan di Kesultanan Cirebon adalan Keraton Kasepuhan.
Kasepuhan berasal dari kata bahasa Sunda yaitu “Sepuh” yang berarti “Tua”. Pada
awalnya di Kesultanan atau Kerajaan Cirebon hanya ada satu keraton, yakni
Keraton Pakungwati. Namun di abad ke-17, bersamaan dengan dibaginya
kesultanan menjadi tiga kekuasaan., maka dibangun pula Keraton Kasepuhan dan
Keraton Kanoman. Ketiga keraton tersebut masing-masing berasal dari satu
keturunan anggota Wali Songo,8 yaitu Sunan Gunung Jati. Kesultanan Cirebon
resmi dibagi menjadi Kesultanan Kasepuhan, Kesultanan Kanoman dan satu
7R. Kurnianto & N. Lestarini, “Integration of Local Wisdom in Education”.
In International Seminar on Education, 2020, h. 557-563.; N. Hariyati, “Islamic Education
in the Prespective of Islamic Nusantara”. In International Conference on Language,
Education, Economic and Social Science, vol. 1, no. 1, 2019, h. 125-134.; T. Narawati,
“Arts and Design Education for Character Building”. In International Conference on Arts
and Design Education (ICADE 2018), (Atlantis Press, 2019). 8Wali Songo (Wali Sembilan) adalah kelompok wali atau orang suci yang
mendakwahkan Islam di Pulau Jawa. Menurut literature, umumnya menyatakan bahwa Wali
Songo terdiri dari sembilan orang, di antaranya Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan
Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Drajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan
Muria, dan Sunan Gunung Jati. Lihat Pierre Fournié, “Rediscovering the Walisongo,
Indonesia: A Potential New Destination for International Pilgrimage”. International Journal
of Religious Tourism and Pilgrimage, 7, no. 4, 2019, h. 77-86.; Abdurrohman Kasdi, “The
Role of Walisongo in Developing the Islam Nusantara Civilization”. Addin, vol. 11, no. 1,
2017, h. 1-26.; E. Soenarto, “From Saints to Superheroes: The Wali Songo Myth in
Contemporary Indonesia's Popular Genres”. Journal of the Malaysian Branch of the Royal
Asiatic Society, 2005, h. 33-82.
144
Peguron pada tahun 1679 oleh Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten untuk
menghindari perpecahan keluarga Kesultanan Cirebon.9
Keraton Kasepuhan dulunya adalah keraton Pakungwati. Namun karena
ditempati oleh Sultan Sepuh maka Namanya berubah menjadi Keraton Kasepuhan.
Keraton Kasepuhan memiliki luas wilayah 18,5 hektare. Keraton dibatasi oleh
tembok yang membentang dari utara ke selatan. Untuk memasuki halaman pertama
terdapat jembatan Pangrawit dan pintunya hanya merupakan pemotongan tembok
keliling. Sebelum memasuki halaman pertama terdapat bangunan Pancaratna di sisi
barat dan Pancaniti di sisi timur jalan masuk. Pada halaman pertama di sisi timur
terdapat kompleks Siti Inggil dan pintu Penggada. Untuk memasuki halaman ke dua
terdapat Langgar Dalem di sisi barat, melalui dua Gapura Paduraksa. Selanjutnya
adalah zona semi privasi, tempat Sultan bekerja dan menerima tamu. Area ini bisa
dimasuki melalui pintu Gledegan. Terakhir adalah area privat Sultan dan
keluarganya. Di area ini Sultan dan keluarganya tinggal sehingga tidak sembarang
orang bisa masuk. Area ini bisa dimasuki melalui pintu Buk Bacem.10
Berdasarkan penelusuran dan observasi penulis, ruang Keraton Kasepuhan
mengadopsi seni bangunan yang berkembang pada masa Majapahit. Di samping itu,
masih adanya kepercayaan alam pikiran pada masa pra Islam tentang kesejajaran
antara alam semesta dan alam manusia. Kosmo magis yang berasal dari ajaran
kosmologis Hindu-Buddha. Gambaran atau cerminan alam semesta menurut
kepercayaan itu adalah bahwa keraton dan semua isi di dalamnya dianggap sebagai
replika atau tiruan alam semesta. Misalnya, seorang raja yang sedang bersemayam
di dalam keraton disamakan dengan dewa yang bersemayam di puncak Mahameru.
Salah satu pengejawantahan kepercayaan peniruan kosmos Mahameru melalui seni
bangunan yang sangat menonjol adalah bangunan candi.11
Dengan demikian,
penggambaran gunung merupakan suatu motif yang mewisesa dalam seni bangunan
Jawa-Hindu.
Dalam konteks di atas, salah satu ciri penting lainnya yang juga dianggap
sebagai kesinambungan alam pikiran Jawa-Hindu yang mengilhami atau
berpengaruh pada perkembangan seni bangunan Keraton Kasepuhan adalah
pembuatan gunung atau bukit dan kolam buatan dengan suatu gugusan bangunan
yang terletak di tangannya. Dua buah gunung buatan di dalam Keraton Kasepuhan
disebut gunung Semar dan gunung Indrakila, sedangkan bagian dalam bangunan
kolam buatan dengan gugusan bangunan di tengahnya disebut Balong Klangenan.
Sementara bangunan kayu di tengahnya disebut Bale Kembang.12
Aspek lainnya
9Atja, Carita Purwaka Caruban Nagari: Karya Sastra sebagai Sumber Pengetahuan
Sejarah, (Bandung: Proyek Pemuseuman Jawa Barat, 1986), h. 74. 10
Dini Rosmalia, “Pola Ruang Lanskap Keraton Kasepuhan Cirebon”, Seminar Heritage
IPLBI, 2018, h. B 074-082. 11
Dini Rosmalia &L. Edhi Prasetya, “ Kosmologi Elemen Lanskap Budaya Cirebon”, Seminar
Heritage IPLBI, 2017, h. B 073-082. 12
I. H. Agustina, A. Djunaedi, S. Sudaryono, & D. Suryo, “The Perspective of
Sustainable in Relation Space at Region of Kasultanan Kasepuhan Cirebon”, Makalah
dipresentasikan dalam International Conference ICABE di IIUM, Kuala Lumpur, 7th–8th
November, 2013. Lihat juga I. H. Agustina, A. Djunaedi, S. Sudaryono, & D. Suryo, “Gerak
Ruang Kawasan Keraton Kasepuhan”. Jurnal Perencanaan Wilayah dan
145
adalah tata letak bangunan kompleks Keraton Kasepuhan dapat dibagi ke dalam tiga
bagian. Kontur permukaan dan pelataran kompleks keraton dibuat semakin
meninggi ke belakang, yang menunjukan derajat kesucian dan merupakan bagian
paling suci, karena bagian ini merupakan tempat bersemayam raja beserta seluruh
keluarganya. Struktur kosmologi Keraton Kasepuhan digambarkan Agustina,
Hindersah dan Asiyawati13
sebagai berikut:
Gambar 4. Struktur Kosmologi Keraton Kasepuhan
Sumber: Agustina, Hindersah, & Asiyawati, 2017:167-174
Ketika memasuki kawasan Keraton Kasepuhan,14
kita akan melihat sebuah
gerbang yang terbuat dari batu bata merah bertingkat. Bagian paling depan keraton
disebut Siti Inggil atau tanah tinggi, yang kedudukannya menghadap langsung ke
arah lapangan tempat pasukan keraton ketika itu berkumpul setelah melewati Siti
Inggil yang berbentuk gerbang dan pagar panjang. Di bagian depan Siti Inggil juga
terdapat meja dan bangku yang terbuat dari batu. Benda tersebut berasal dari
Gujarat dan merupakan hadiah dari Gubernur Jenderal Inggris, Sir Thomas
Stamford Raffles15
di tahun 1811 M. Bangunan Siti Inggil merupakan perpaduan
dari Islam, Hindu, dan Tiongkok. Di bagian tembok Siti Inggil terdapat banyak
tempelan keramik Tiongkok, di samping juga terdapat keramik Belanda. Gapura
Siti Inggil mendapat pengaruh Hindu karena jika diperhatikan bentuk bangunannya
sama seperti Gapura Candi Bentar.
Kota, vol. 13, no. 1, 2013, h. 8-13.
13I. H. Agustina, H. Hindersah, & Y. Asiyawati, “Identifikasi Simbol-Simbol Heritage
Keraton Kasepuhan”. ETHOS: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, vol.
5, no. 2, 2017, h. 167-174. 14
Keraton Kasepuhan dibangun pada tahun 1430 M. 15
Sir Thomas Stamford Raffles (1781-1826) pernah menjadi Gubernur Jenderal van
Java (1813-1818). Lihat S. Raffles, Memoir of the Life and Public Services of Sir Thomas
Stamford Raffles, (New York: Cambridge University Press, 2013).; C. H. Wake, “Raffles
and the rajas: the founding of Singapore in Malayan and British colonial history. Journal of
the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, vol. 48 (227), 1975, h. 47-73.
146
Gambar 5. Siti Inggil
Sumber: Dokumentasi Mukhoyyaroh, 2020
Siti Inggil sebagaimana gambar di atas dikelilingi tembok bata merah dengan
tempelan piring keramik dan pintu masuk berupa Candi Bentar. Dilihat dari bentuk
dan ornamen yang menghiasi bangunan Siti Inggilmengadopsi budaya dari Hindu
berupa Candi Bentar dan budaya dari Tiongkok berupa tempelan piring keramik.
Strukturnya berupa tumpukan bata merah yang saling ditempelkan antara satu dan
lainnya.
Pemasangan piring keramik dari Tiongkok dalam banyak tempelan pada
bangunan Keraton Kasepuhan, termasuk pada bangunan Siti Inggil dalam berbagai
literatur erat kaitannya dengan kebudayaan Islam.16
Berthold Laufer (1874-1934),
seorang antropolog yang bekerja di Filipina, adalah orang pertama yang
memberikan perhatian khusus pada serpihan keramik Tiongkok untuk studi
pertukaran komersial dan budaya.17
Memang, pada awal abad ke-20, perdagangan
antara Tiongkok dan Asia Tenggara, serta antara Tiongkok dan dunia Muslim,
sedang mengalami kemajuan.18
Laufer kemudian mengusulkan untuk memasukkan
keramik Tiongkok di antara bahan historis untuk mempelajari pola perdagangan.
Laufer mengatakan selain dari referensi kronologis yang secara khusus menarik
minat para arkeolog, studi tentang keramik Tiongkok berkaitan dengan dua tingkat
sejarah, yakni menyangkut distribusi spesial artefak, serta periuk19
dan porselen
yang lebih awet daripada kebanyakan jenis barang lainnya. Kemunculannya di
seluruh situs arkeologi di Samudra Hindia menawarkan serangkaian data geografis
yang tepat untuk menciptakan kembali lintasan perdagangan maritim. Dengan
16
J. G. Tylor, “The Chinese and the Early Centuries of Conversion to Islam in
Indonesia”. In Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting, T. Lindsey & H.
Pausacker (ed.), (Singapore & Australia: ISEAS Publication & Monash University Press,
2005), h. 148-164. 17
B. Laufer, “Post Scriptum”. In F. C. Cole, Chinese Pottery in the Philippines, Field
Museum of Natural History, Anthropological Series, vol. XII, no. 1, 1912. 18
Danar Widiyanta, “Keberadaan Etnis Cina Dan Pengaruhnya Dalam Perekonomian Di Asia Tenggara”, Mozaik, Vol. V, No. 1, 2010, h. 84-95.
19Periuk adalah peralatan dapur yang sampai saat ini masih dapat ditemukan di daerah
perkampungan. Para penduduk masih menggunakannya karena selain bentuknya indah,
periuk dibuat dari bahan tembaga yang dipercaya lebih tahan lama ketimbang bahan yang
terbuat dari logam dan sejenisnya. Penelitian terkait jenis periuk bisa dilihat dalam karyanya
B. Zhao, “Chinese-style ceramics in East Africa from the 9th to 16th century: A case of
changing value and symbols in the multi-partner global trade”. Afriques. Débats, Méthodes
et Terrains D‟histoire, no. 06, 2015.
147
menggunakan pendekatan ini, para sarjana Jepang dan Eropa seperti Mikami20
dan
Pirazzoli-t‟Serstevens21
menggunakan istilah “Jalan Keramik” untuk menunjuk rute
perdagangan maritime.
Karena produksi periuk cukup signifikan di semenanjung Asia Tenggara terkait
erat dengan tradisi Tionghoa, hal ini membuat beberapa sarjana telah mengusulkan
untuk memberi label ulang kaitannya dengan penggunaan istilah “keramik gaya
Tiongkok”.22
Sebagaimana penelitian Zhao, memilih untuk menggunakan istilah
umum “keramik gaya Tiongkok” sebab produksi keramik di Asia Timur adalah
transnasional dan global dan didasarkan pada konteks perdagangan yang kompleks.
Pertama, selama periode dari abad ke-11 hingga ke-16, hubungan antara kekaisaran
Tiongkok, negara-negara tetangga di Asia Tenggara, dan perbatasan mereka
berkembang secara signifikan. Kedua, provinsi-provinsi Tiongkok di Guangxi,
Yunnan, dan Guangdong dan negara-negara di semenanjung Asia Tenggara
diuntungkan oleh kondisi iklim yang serupa, di mana produksi keramik sangat
bergantung.
Fleisher dan Laviolette mengatakan sejak akhir abad ke-13 dan seterusnya,
kehadiran keramik gaya Tiongkok di bagian utama masjid telah diperhatikan oleh
para arkeolog di beberapa lokasi. Para ahli berpendapat untuk penggunaan paralel
gaya keramik Tiongkok dalam konteks agama dan domestik adalah bahwa
keduanya mungkin terkait erat dengan Islam.23
Kaitannya dengan konteks penelitian
ini, keramik-keramik gaya Tiongkok dapat ditemukan di Keraton Kasepuhan
sekaligus menjadi saksi hubungan antara orang-orang keraton dengan etnis
Tionghoa, misalnya guci-guci atau tempelan-tempelan keramik yang ada di
bangunan keraton, Astana Gunung Jati, Masjid Gunung Jati dan Guha Sunyaragi.
Selain itu, banyak cara untuk melihat fungsi keramik Tiongkok membuktikan
daya tarik material yang tidak terbantahkan. Penulis mencontohkan, banyak artefak
Tiongkok memiliki lubang paku keling di dalamnya untuk mengakomodasi kabel
logam yang bergabung kembali dengan pecahan. Lubang tersebut umumnya
menurut Pirazzoli-T‟Serstevens ditafsirkan sebagai indikasi bahwa benda-benda ini
sangat berharga.24
Piringan keramik Tiongkok yang dipangkas dengan serpihan
keramik Tiongkok dan Islam juga telah digali, beberapa di antaranya dilubangi di
20
Ts. Mikami, Tôji no michi – tôzai bunmei no setten o tazunete [Jalan Keramik: Bukti
Materiel dari Kontak Budaya Timur dan Barat], (Tokyo: Iwnami Shoten, 1969). 21
M. Pirazzoli-t‟Serstevens, “La route de la céramique”, Le grand Atlas de
l‟archéologie, (Paris: Encyclopaedia Universalis, 1985), h. 284-285. 22
M. F. Dupoizat, N. H, Wibisono, C. Guillot, Catalogue of the Chinese-Style
Ceramics of Majapahit: Tentative Inventory, (Paris & France: Association Archipel, 2007). 23
J. Fleisher, A. Laviolette, “The Changing Power of Swahili Houses, Fourteenth to
Nineteenth Centuries AD”. In R. A. Beck (ed.), The durable house: House Society Models in
Archaeology, Center for Archaeological Investigations Occasional Paper, no. 35,
(Carbondale, Southern Illinois University, 2007), h. 175-197. 24
M. Pirazzoli-T‟serstevens, “Une Denrée Recherchée: la Céramique Chinoise
Importée dans le Golfe Arabo-persique, IXe–XIV
e Siècles”. Mirabilia Asiatica, vol. 2, 2005,
h. 69-88.
148
tengahnya.25
Tampaknya benda-benda tersebut digunakan sebagian untuk menghiasi
tubuh dan pakaian, seperti liontin, anting-anting, dan kancing. Sangat menarik
untuk memerhatikan bahwa pecahan artefak yang dipilih untuk penggunaan
sekunder ini umumnya didekorasi dengan glasir berkilauan yang berwarna-warni.26
Adapun pecahan keramik dapat diubah menjadi alat (weights, spindle whorls, dan
sebagainya). Dalam konteks itu mereka membuktikan bahwa periuk dan porselen
sangat dihargai. Studi terbaru tentang konteks arsitektur non-batu ditambah dengan
survei pedesaan membuktikan bahwa periuk dan serpihan porselen juga digunakan
untuk menghias dinding rumah dari tanah liat.27
Bagi Li Min, fenomena ini
merupakan contoh konkrit dari akulturasi, menggambarkan bagaimana keramik
Tiongkok telah mengalami transformasi fungsional dan kadang-kadang bahkan
gaya ketika mereka disesuaikan kembali dengan budaya material lokal.28
Dengan demikian, jelas bahwa bukti arkeologis yang tersedia mengungkapkan
difusi keramik gaya Tiongkok ke daerah Cirebon, khusunya Keraton Kasepuhan
tampaknya terkait dengan penetrasi Islam, karena ditemukan keramik-keramik gaya
Tiongkok di Keraton Kasepuhan yang merupakan kesultanan Islam. Keramik-
keramik dapat dilihat pada bangunan keraton, Astana Gunung Jati, Masjid Gunung
Jati dan guha Sunyaragi. Selain itu penulis melihat ada peran yang sama dengan
simbol sosial, karena impor ini ditemukan dalam konsentrasi tinggi di makam elit
yang terlibat dalam perdagangan maritim. Barang-barang eksotis ini juga berfungsi
sebagai simbol dan perwujudan kekuatan dagang.
Berbagai bukti arkeologis sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, juga
memperlihatkan bahwa di dalam Keraton Kasepuhan terdapat berbagai budaya yang
ikut mewarnainya. Makna filosofisnya adalah bahwa sekalipun Cirebon merupakan
Kesultanan Islam, tetapi sangat terbuka terhadap dinamika masyarakat, dan bersikap
inklusif terhadap berbagai budaya dan keberagamaan orang lain. Kesultanan ini
ingin berdiri di atas keberagaman budaya, dan meletakkan penghormatan yang
tinggi terhadap keyakinan orang lain. Sebagai contoh, salah satu bangunan paling
depan Keraton Kasepuhan, yakni tembok Siti Inggil. Di tembok Siti Inggil ada
25
S. Pradines, Fortifications et Urbanisation en Afrique Orientale, (Oxford:
Archaeopress, 2004). 26
Untuk cakram berlubang yang dibuat dengan periuk hijau Longquan dengan pola
naga ditemukan di situs Kilwa-Kisiwani, lihat N. Chittick, Kilwa: An Islamic Trading City
on the East African Coast, vol. II, (Nairobi/London: British Institute of African Studies,
1974), h. 428. 27
L. W. Donley-Reid, “The power of Swahili Porcelain, Beads and Pottery”. In S. M.
Nelson, A.B. Kehoe (eds.), Powers of Observation: Alternative Views in Archaeology,
Archaeological Papers of the American Anthropological Association 2, (Washington:
American Anthropological Association, 1990), h. 47-59. 28
Li Min, “The Trans-Pacific Extension of Porcelain Trade in the Early Modern Era:
Cultural Transformations Across Pacific Space”. In P. K. Cheng (ed.), Proceeding of the
International Symposium: Chinese Export Ceramics in the 16th and 17th Centuries and the
Spread of Material Civilisation, (Hong Kong: The City University, 2012), h. 219-234.
149
Gapura Candi Bentar, tempelan keramik Tiongkok dan keramik Belanda.29
Ornamen-ornamen tersebut diletakkan di bagian paling depan dari Keraton
Kasepuhan sehingga dapat disaksikan oleh semua orang.
Candi Bentar sebagaimana di Siti Inggil (Keraton Kaespuhan) yang
mengadopsi budaya dari Hindu banyak ditemukan di beberapa tempat di Indonesia
dengan pemaknaan yang berbeda-beda, misalnya Yusuf dalam penelitiannya
mengatakan bahwa Candi Bentar dalam konsep Bali merupakan simbol mulut yang
tenganga. Simbol mulut yang tenganga ini menjadikan Candi Bentar sebagai pintu
masuk. Yusuf mencontohkan Candi Bentar pada kompleks gereja Kristen Pniel
Blimbingsari, Bali. Candi Bentar pada gereja ini memiliki ornamen salib sebagai
simbol agama Kristen.30
Sementara Zarifa dalam penelitiannya tentang “Masjid dan
Makam Sendang Duwur: Perwujudan Akulturasi”, mengatakan bahwa terdapat 4
Candi Bentar pada kompleks masjid dan makam Sendang Duwur. Candi Bentar
dikenal pada zaman Indonesia–Hindu, seperti terdapat pada bekas kompleks
Keraton Majapahit (Gapura Waringin Lawang). Bangunan kuno (Candi) relief
seperti itu terdapat pada relief Candi Jawi, Candi Jago, dan Candi Tigawangi. Zarifa
bahkan mengatakan bahwa Candi Bentar yang tertua berada di Pura Prasada Bali.31
Perpaduan budaya Islam dan Hindu menjadi satu kesatuan yang saling
melengkapi yang diwujudkan dalam bentuk bangunan yang dalam konteks Keraton
Kasepuhan, salah satunya adalah Siti Inggil. Sebagaiman juga penelitian Fitri terkait
Gapura Bentar, Gapura Paduraksa, masjid dan makam di Sendang Duwur,32
Lamongan, Jawa Timur. Fitri dalam penelitiannya mengatakan bahwa di bangunan
paduraksa terdapat ornamen dan motif yang memiliki makna simbolik dalam
kaitannya dengan Islam, misalnya hiasan motif pohon kalpataru yang dalam
kepercayaan Hindu menyebutnya sebagai pohon hayat, sedangkan dalam Islam
disebut pohon syajarotul khuldi yang berada di sidrotul muntaha. Pohon tersebut
mempunyai makna bahwa pohon yang dapat memberikan segala keinginan.33
Dalam konteks Kesultanan Cirebon, Gapura Candi Bentar yang mendapat
pengaruh Hindu bermakna bahwa Kesultanan Cirebon sekalipun merupakan
kesultanan Islam tetapi sangat menghormati dan menghargai leluhurnya dengan
tetap mengakomodir unsur-unsur budaya Hindu. Sehingga orang Hindu yang
29
Pembahasan tentang tempelan keramik Belanda dalam kajian ini tidak dijelaskan
secara spesifik sebab keramik ini dipasang belakangan setelah kehadiran Belanda di
Cirebon. 30
S. A. Yusuf, “Aspects of Architecture Infrastructures Acculturation Function, form
and the Meaning of the Christian Church building Pniel Blimbingsari in Bali. Arteks: Jurnal
Teknik Arsitektur, vol. 1, no. 1, 2016, h. 15-30. 31
A. P. Zarifa, “Masjid dan Makam Sendang Duwur: Perwujudan Akulturasi”. In
Prosiding Seminar Heritage IPLBI, 2017, h. 381-384. 32
Sendang Duwur diambil dari salah satu nama tokoh yang menyebarkan Islam di
tanah Jawa, yakni Sunan Sendang Duwur. Nama asli dari Sunan Sendang Duwur adalah
Raden Noer Rahmanputra dari Abdul Kohar bin Malik bin Sultan Abu Yazid dari
Baghdad. Gelar Sunan Sendang Duwur didapat dari pemberian Sunan Drajad. 33
R. F. R. Fitri, “Simbol Bangunan pada Komplek Gapura, Masjid dan Makam
Sendang Duwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur”. Jurnal
Penelitian, Universitas Airlangga, 2018, h. 1-10.
150
melihat Gapura Candi Bentar merasakan keterwakilannya, begitupun etnis
Tionghoa ketika melihat ornamen-ornamen Tionghoa. Lebih jauh kesultanan ini
menginginkan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup berbudaya
dalam kehidupan bernegara. Ini menandakan bahwa sejak awal Kesultanan Cirebon
yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati menjadi basis bagi pengembangan Islam
yang toleran, inklusif,34
atau dalam bahasa yang sedang booming sekarang ini, yakni
Islam Wasathiyyah atau Islam moderat.
Kaitannya dengan konsep Islam Wasathiyyah sebagaimana di atas,
cendekiawan Muslim Azyumardi Azra membuat sebuah penegasan dengan
mengatakan bahwa Islam Wasathiyyah atau Islam moderat secara substansi
merupakan tradisi lama, baik secara keagamaan atau kebudayaan. Lebih lanjut ia
mengatakan bahwa Islam Wasathiyyah sudah diperkenalkan oleh para ulama
terdahulu, terhitung sejak kehadirannya di Nusantara. Wasathiyyah Islam bertemu
dengan ragam budaya dan suku bangsa, yang menekankan pada sikap “tengahan”
melahirkan umat Islam Indonesia yang wasathiyyah, akomodatif dan inklusif.
Sebagai contoh budaya masyarakat Jawa yang tepo seliro, guyub adalah budaya
yang menekankan pada kebersamaan, tidak “menang-menangan”, tidak egois dan
tidak menang sendiri. Islam Wasathiyyah atau Islam moderat yang berkembang di
Indonesia memiliki beberapa karakteristik yaitu tawassuth, tawazun, dan
muwathonah.35
Istilah wasathiyyah merupakan terminologi yang sangat dinamis dan
kontekstual. Artinya, terminologi tersebut tidak hanya berkaitan dengan satu aspek
saja, tetapi melibatkan keseimbangan antara pikiran dan wahyu, materi dan spirit,
hak dan kewajiban, individualisme dan kolektivisme, teks (al-Qur‟an dan hadis) dan
ijtihad, ideal dan realita, yang permanen dan sementara,36
yang kesemuanya terjalin
secara terpadu. Dengan demikian, sebenarnya konsep Islam Wasathiyyah atau Islam
moderat meminta umat Islam untuk mengamalkan ajaran Islam secara seimbang,
tidak berlebihan dan komprehensif dalam berbagai hal dengan memusatkan
perhatiannya pada peningkatan kualitas kehidupan manusia yang terkait dengan
pengembangan pengetahuan, pembangunan manusia, sistem ekonomi dan
keuangan, sistem politik, sistem pendidikan, kebangsaan, pertahanan, persatuan,
persamaan antar ras dan lainnya.37
Pada akhirnya, Islam Wasathiyyah harus menjadi
34
Toleran dan inklusifnya Kesultanan Cirebon tidak terlepas dari sosok pemimpinnya,
yaitu Sunan Gunung Jati. Sikap Sunan Gunung Jati yang toleran dan inklusif menurut
Irianto erat kaitannya dengan wawasannya yang luas dan bersifat internasional, ilmunya
“dalam”, sudah mengunjungi banyak negara, serta sahabatnya lintas agama dan negara.
Itulah yang membentuk kepribadian Sunan Gunung Jati. Wawancara dengan Bambang
Irianto (Budayawan Cirebon) pada tanggal 08 Juli 2020. 35
Azyumardi Azra, disampaikan dalam Webinar yang diselenggarakan PPIM Jakarta,
19 Juni 2020. 36
Yusuf Qardhawi, Thaqafatuna Bayna Al-Infitah Wa Al-Inghilaq, (Cairo: Dar al-
Shuruq, 2000), h. 30. 37
Mohd Shukri Hanapi, “The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic
Epistemology: A Case Study of its Implementation in Malaysia”. In International Journal of
Humanities and Social Science, vol. 4, no. 9, 2014, h. 51-62.
151
arus utama keislaman di Indonesia, karena dianggap menjadi solusi untuk
menjawab berbagai problematika keagamaan dan peradaban global.38
Kajian Islam dalam konteks Islam Indonesia yang moderat juga erat kaitannya
dengan konsep moderasi. Hilmy mengatakan konsep moderasi memiliki beberapa
karakteristik di antaranya: Menyebarkan Islam tidak menggunakan kekerasan, tetapi
lebih mengutamakan jalan damai; Mengadopsi cara hidup yang moderat dalam
semua aspek, termasuk sains dan teknologi, demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM)
dan sejenisnya; Cara berfikirnya rasional; Dalam memahami Islam sangat
kontekstual, tidak tekstual; dan, menggunakan ijtihad jika tidak ditemukan
justifikasi eksplisit dari al-Qur‟an dan hadis. Beberapa karakteristik tersebut bisa
diperluas dengan beberapa karakteristik lain seperti toleransi, harmoni dan kerja
sama antar kelompok agama.39
Sekalipun istilah Islam moderat atau Islam Wasathiyyah baru populer
belakangan ini dan mendapat momentumnya pada masa Lukman Saefuddin
(Menteri Agama RI 2014-2019), namun dalam konteks kajian ini penulis melihat
“ruh”nya sudah ada sejak Kesultanan Cirebon didirikan. Corak Islam yang inklusif,
akomodatif dan toleran terhadap keberagaman agama dan budaya yang diwariskan
oleh para pendiri Kesultanan Cirebon masih bisa kita saksikan bersama dalam
beberapa tempat bersejarah di Cirebon. Jika Kesultanan Cirebon itu ekslusif tentu
kita tidak akan menemukan budaya-budaya dari luar yang notabene budaya non-
Islam ada dan berakulturasi dengan budaya Islam, bahkan menempel di bangunan-
bangunan yang dimuliakan dan disakralkan oleh warga masyarakat setempat.
Sebagaimana yang dijelaskan di atas, di tembok bangunan utama Keraton
Kasepuhan yaitu Siti Inggil, terdapat Gapura Candi Bentar yang mendapat pengaruh
dari Hindu, dan keramik-keramik yang berasal dari Tiongkok. Berdasarkan
posisinya, kedua wujud budaya tersebut diletakkan di bagian depan, serta Gapura
Candi bentar dan pengaruh Hindu lainnya diletakkan di atas atau lebih tinggi.
Secara sombolik hal tersebut erat kaitannya dengan waktu kedatangan Hindu yang
sudah lebih dulu dibanding Islam. Adapun keberadaan tempelan-tempelan keramik
Tiongkok yang dipasang di tembok bagian depan keraton bermakna bahwa Keramik
Tiongkok itu merupakan budaya dari luar, bukan budaya lokal. Oleh karena budaya
tersebut datang dari luar, maka tempelan keramik diletakkan di tembok bagian
depan Kesultanan Cirebon dan diletakkan di luar. Sedangkan keberadaan keramik-
keramik Tiongkok di bagian dalam Keraton Kasepuhan memperlihatkan eksistensi
etnis Tionghoa yang kemudian menjadi isteri Sultan Gunung Jati, yakni putri Ong
Tien. Oleh karena itu, tidak heran jika sampai sekarang pengaruh budaya Tionghoa
tidak hanya ada di luar, namun juga di dalam keraton. Hal tersebut bermakna bahwa
budaya Tionghoa telah menjadi bagian penting dan integral dari Kesultanan
Cirebon yaitu dengan terjadinya perkawinan antara Sunan Gunung Jati dan Puteri
38
Sauqi Futaqi, “Konstruksi Moderasi Islam (Wasathiyyah) dalam Kurikulum
Pendidikan Islam”. In 2nd Proceedings; Annual Conference for Muslim Scholars, UIN
Sunan Ampel Surabaya, 21-22 April 2018, h. 521-530. 39
Masdar Hilmy, “Whither Indonesia‟s Islamic Moderatism? A reexamination on the
moderate vision of Muhammadiyah and NU”. Journal of Indonesian Islam, vol. 7, no. 1,
2013, h. 24-48.
152
Ong Tien. Sebagaimana dikatakan oleh Opan bahwa akulturasi yang paling tinggi
adalah melalui perkawinan.40
Hal ini juga diamini oleh Gillin. Menurutnya
perkawinan campur adalah kondisi yang paling menguntungkan untuk proses
akulturasi.41
Seandainya sultan tidak beristerikan orang Tionghoa, boleh jadi
budaya-budaya Tionghoa itu tidak akan mewarnai Keraton Kasepuhan. Lebih lanjut
Opan juga mengatakan bahwa pada saat itu barang atau produk-produk dari
Tiongkok terutama keramik dikenal sangat bagus baik motif maupun kualitasnya.
Semua orang-dari sultan sampai rakyat- menyukai motif atau ornamen yang ada di
keramik atau sutera yang dibawa Ong Tien. Kemudian dalam perkembangannya
ornamen-ornamen itu ikut mewarnai dan memengaruhi budaya-budaya yang
berkembang di Cirebon. Pendapat ini juga diperkuat oleh pernyataan P.R. A Arief
Natadiningrat bahwa kebudayaan Tiongkok mulai berpengaruh secara signifikan
terhadap kebudayaan Cirebon sejak kedatangan puteri Ong Tien.42
Dengan demikian, Candi Bentar yang merupakan pengaruh dari Hindu di
Indonesia telah terakulturasi dengan kebudayaan Islam, khususnya di Gapura Siti
Inggil kompleks Keraton Kasepuhan Cirebon dan di tempat-tempat lain, seperti
makam dan masjid Sendang Duwur sebagaimana penelitian Zarifah serta Candi
Bentar pada gereja di Bali yang memiliki ornamen salib.
Bangunan Siti Inggil tidak hanya mendapat pengaruh Hindu tapi juga budaya
Tionghoa. Budaya Tionghoa kaya akan makna dan simbol, khususnya yang
berkaitan dengan hewan. Budaya Tionghoa juga dipengaruhi oleh agama Budha,
Tao dan Khong Hucu sebagai agama mayoritas masyarakat Tionghoa. Dalam kitab
Tripitaka seperti yang ditulis Mulyono dan Diana menjelaskan bahwa Sang Buddha
sangat menghargai nyawa makhluk hidup, tidak terkecuali binatang. Oleh karena
itu, masyarakat Tionghoa menjadikan hewan sebagai komponen-komponen
simbolik dan sering mengkaitkan sifat-sifat hewan dengan nilai-nilai kehidupan
manusia. Hewan dianggap memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai hidup
yang ingin digapai oleh manusia, yakni kesehatan, panjang umur, kekuatan,
kemakmuran, dan perlindungan dari segala bahaya.43
Begitupun dengan gambar-
gambar yang menghiasi keramik-keramik yang menempel di tembok Siti Inggil
kaya akan simbolisasi yang dikaitkan dengan budaya Tionghoa. Adapun gambar-
gambar yang menempel di keramik adalah naga (lung), phoenix (feng huang), dan
ikan.
Naga dalam zodiak Tiongkok adalah makhluk luar biasa yang melambangkan
kemakmuran dan keperkasaan. Naga juga merupakan simbol dari Kaisar Tiongkok,
di mana mereka selalu mengenakan jubah yang penuh dengan ornamen naga.
Sementara dalam tradisi Tionghoa, naga identik dengan sesuatu yang besar dan
40
Wawancara dengan Opan Safari (Filolog dan Budayawan Cirebon) pada tanggal 19
Juli 2020. 41
Gillin&Gillin, Cultural Sociology: A Revision and of Introduction to Sociology, (New York: The Mac Millan Company, 1948), h. 530. 42
N. Sofiyawati, Kajian Gaya Hias Singa Barong dan Paksi Naga Liman Dalam Estetika Hibriditas Kereta Kesultanan Cirebon, Sosioteknologi, Vol. 16, No. 3, 2017, h. 304-324
43Grace Mulyono dan Diana Thamrin, “Makna Ragam Hias Binatang pada Klenteng
Kwan Sing Bio di Tuban”. Dimensi Interior, vol. 6, no. 1, 2008, h. 1-8.
153
hebat.44
Menurut Bambang Irianto Naga itu khusus untuk pemimpin. Untuk
pemimpin nomor satu biasanya naganya menghadap kedepan. Jadi, seorang Patih,
Tumenggung atau Bupati sekalipun tidak akan berani menggunakan jubah atau baju
dengan ornamen naga yang menghadap kedepan. Biasanya selain raja atau sultan,
ornamen naganya menghadap kesamping. Hal itu bisa disaksikan pada Kereta
Kencana Singa Barong yang banyak terdapat patung naga, yang semuanya
menghadap kedepan.45
Artinya Kereta kencana Singa Barong adalah kendaraan
yang khusus diperuntukkan untuk Sultan. Makanya, tempat duduknya hanya untuk
satu orang.
Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, naga merupakan penggabungan dari
sembilan macam hewan yang dikomposisikan sedemikian rupa, yaitu; 1) kepala
menyerupai unta, dengan jenggot panjang dan lidah mematikan; 2) tanduk unta; 3),
mata kelinci; 4) telinga sapi yang tidak dapat mendengar; 5) leher ular; 6) perut
katak; 7) sisik ikan pada tubuh; 8) sayap elang; dan 9) tapak kaki harimau.46
Naga
memiliki arti yang sangat berharga bagi masyarakat Tionghoa. Simbol naga
melambangkan nilai-nilai kebajikan yang dijunjung tinggi. Pada intinya, naga
adalah simbol kebesaran, keagungan dan kehebatan; simbol kemakmuran akan air,
baik melalui hujan ataupun danau; simbol dari kekuatan yang menjaga dan
mengawasi manusia serta jagad raya.47
Sementara menurut Tanomi, naga dianggap sebagai Dewa Laut dan Dewa yang
bisa mendatangkan hujan oleh orang Tiongkok Kuno. Mereka sangat menghormati
naga, apalagi mereka sangat tergantung pada hasil pertanian. Lebih lanjut mereka
menganggap naga sebagai lambang keberuntungan, kemakmuran, kekuasaan,
keberanian, kepercayan dan kepahlawanan. Pertunjukan Liong pada saat Cap Go
Meh adalah salah satu wujud tradisi untuk berdoa meminta perlindungan dari sang
naga.48
Dalam konteks Keraton Kasepuhan, naga dijumpai pada tembok Siti Inggil
sebagai bangunan utama dan paling depan, yang secara filosofis bermakna bahwa
Kesultanan Cirebon merupakan kesultanan yang berdiri sendiri bukan kerajaan
44
Mulyono dan Thamrin, “Makna Ragam Hias Binatang pada Klenteng Kwan Sing Bio
di Tuban”, h. 1-8. 45
Wawancara dengan Bambang Irianto (Budayawan Cirebon) pada tanggal 08 Juli
2020. 46
Li Xiaoxiang, Origins of Chinese People and Customs, (Jakarta: PT. Elex Media
Komputindo, 2003), h. 22-25.; Lihat juga Polniwati Salim, “Memaknai Pengaplikasian
Ornamen pada Atap Bangunan Klenteng sebagai Ciri Khas Budaya Tionghoa”. Aksen, vol 1,
no. 2, 2016, h. 50-65.; Mulyono dan Thamrin, “Makna Ragam Hias Binatang pada Klenteng
Kwan Sing Bio di Tuban”, h. 1-8.; Sugiri Kustedja, dkk., “Makna Ikon Naga, Long, Elemen
Utama Arsitektur Tradisional Tionghoa”. Jurnal Sosioteknologi, ed. 30, thn. 12, 2013, h.
526-539. 47
De Jeny Gex, Asian Style Source Book, (Singapura: MQ Publication Ltd., 2000), h.
44-45. 48
Erna Tanomi dan Elisa Christiana, “Akulturasi Budaya Tionghoa dan Jawa dalam
Pertunjukan Liong Batik dan Wacinwa di Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta tahun 2015”.
Century: Journal of Chinese Language, Literature and Cultur, vol. 2, no. 1, 2014, h. 108-
122.
154
bawahan Pajajaran seperti Ketika masih dibawah kepemimpinan Cakrabuana. Sejak
Syarif Hidayatullah memimpin Cirebon sudah melepaskan diri dari Pajajaran dan
menjadi negara yang berdaulat penuh.49
Naga yang berada di tembok Siti Inggil
juga bermakna sebagai sebuah doa kepada Kekuatan yang transenden agar
senantiasa menjaga dan melindungi penghuni keraton khususnya keluarga sultan
dan masyarakat Cirebon pada umumnya dari segala macam bahaya, wabah, musuh
dan kemudharatan lainnya. Makna implisitnya adalah bahwa seorang raja atau
pemimpin harus mampu mengayomi dan melindungi warganya dari segala macam
bahaya, baik bahaya musuh, kelaparan, penyakit, kebodohan maupun
kemudharatan. Seorang pemimpin harus mampu memberikan rasa aman, kedamaian
dan kesejahteraan kepada rakyatnya.
Selain gambar naga, di tembok Siti Inggil juga terdapat gambar phoenixsalah
satu simbol penting dalam tradisi masyarakat Tionghoa. Makhluk ini digambarkan
sebagai burung yang indah dengan perpaduan beberapa warna. Makhluk ini
dianggap dapat membawa nasib baik dan melambangkan kaisar wanita, kedamaian
dan kemakmuran. Phoenix juga melambangkan matahari dan kehangatan yang
menyelimuti daerah selatan karena memang makhluk ini merupakan simbol dari
daerah selatan. Menurut Tatt ada beberapa nilai dan makna dari phoenix, yaitu:
penanda lahirnya “orang besar”, phoenix hanya akan singgah ke sesuatu yang
berharga, membawa kemakmuran, kedamaian dan kenyamanan, juga mampu
melawan kejahatan. Dalam upacara perkawinan masyarakat Tionghoa, gambar
phoenix selalu disandingkan dengan naga. Phoenix melambangkan pengantin
wanita, sedangkan naga melambangkan pengantin pria.50
Adapun gambar phoenix
yang ditempel di dinding tembok Siti Inggil bermakna sebuah doa dan harapan agar
kedamaian, ketenangan dan kemakmuran selalu mewarnai kehidupan masyarakat
Cirebon. Masyarakat Cirebon dijauhkan dari segala konflik, pertikaian dan
peperangan. Ketika keadaan negara damai, maka pembangunan di segala bidang
akan berjalan baik, ekonomi juga akan tumbuh cepat, yang pada akhirnya akan
menghantarkan masyarakat Cirebon pada keadaan makmur dan sejahtera.
Gambar yang yang terakhir adalah gambar ikan. Dalam tradisi Tionghoa, ikan
bermakna kegelapan. Hewan ini biasa dihidangkan pada acara Imlek. Maknanya
adalah segala hal yang tidak baik dan kehidupan yang penuh kegelapan atau nasib
buruk di masa lalu harus dihilangkan dan diganti dengan sesuatu yang baik dan
penuh keberuntungan.51
Ikan juga merupakan simbol “berlebih-lebihan”
(kemewahan). Jadi tempelan ornamen ikan di keramik yang ditempel di dinding Siti
Inggil dapat juga diartikan sebagai sebuah doa dan harapan agar masyarakat
49
Atja, Carita Purwaka Caruban Nagari…, h. 95. 50
Ong Hean Tatt, Chinese Animal Symbolisms, (Selangor Darul Ehsan: Pelanduk
Publications, 1993), h. 40-55. 51
Ni Wayan Sartini, “Konsep dan Nilai Kehidupan Masyarakat Tionghoa: Analisis
Wacana Ritual Tahun Baru Imlek”. Masyarakat Kebudayaan dan Politik, vol. 19, no. 2,
2006, h. 47-62.
155
Cirebon senantiasa berada dalam keadaan yang berkecukupan dalam aspek material
dan spiritualnya.52
Sementara dalam bahasa Mandarin ikan sama pelafalannya dengan
keberuntungan.53
Ikan adalah salah satu hewan yang disenangi. Setiap orang yang
melihat ikan hatinya senang dan damai. Makanya dalam kehidupan nyata sering kita
saksikan ada orang-orang yang melarikan “kegalauannya” dengan memancing.
Makna implisit dari gambar ikan adalah bahwa etnis Tionghoa yang datang ke
Cirebon membawa pesan perdamaian dan ingin hidup damai dengan penduduk
setempat, bukan permusuhan atau peperangan. Penulis melihat hal itu sejalan
dengan misi yang dibawa Chengho ketika berkunjung ke Cirebon. Sekalipun saat
itu pasukan yang dibawanya berjumlah, kurang lebih 27.000 pasukan, lebih banyak
dari jumlah penduduk Amparan Jati, namun Cheng Ho tidak melakukan penaklukan
atau kolonialisasi. Cheng Ho hanya membawa misi persahabatan. Makanya di
daerah atau negara manapun ia singgah, diterima dengan baik oleh masyarakat
setempat. Itu yang membedakan kedatangan Cheng Ho dan Barat. Begitupun ketika
Ong Tien datang dengan pasukannya ke Cirebon, membawa misi perdamaian,
bahkan kemudian terjadi perkawinan.
Selain ornamen-ornamen fauna, di keramik-keramik yang ditempel di Siti
Inggil juga ada ornamen flora seperti bunga. Tumbuhan dianggap sebagai lambang
yang memiliki kekuatan alami, dan tahan terhadap berbagai perubahan cuaca atau
iklim. Tumbuhan/bunga yang sering digunakan sebagai ornamen, salah satunya
adalah teratai. Bagi masyarakat Tionghoa terutama pengikut Buddha, teratai
memiliki tempat yang istimewa di hati mereka. Dalam agama Buddha, teratai
dipercaya sebagai tempat duduk Sang Buddha yang melambangkan keagungan.
Teratai dalam budaya Tionghoa melambangkan kesucian dan kesempurnaan, serta
senantiasa tumbuh bersih dan menarik walaupun dalam lumpur atau rawa-rawa.54
Dalam kaitannya dengan Islam, Opan melihat bahwa tiap-tiap orang Muslim di
manapun ia berada, harus mampu menjaga fitrah ketauhidannya, jangan sampai
luntur dan terkontaminasi dengan lingkungan yang membuatnya semakin jauh dari
Dzat Yang Maha Suci. Dengan kata lain, mau berteman dengan siapa saja dan di
mana saja, nilai-nilai Ketuhanan harus selalu dipegang kuat. Manusia harus mampu
beradaptasi dengan lingkungan di manapun berada dan sebisa mungkin bermanfaat
bagi sesama.55
Penulis melihat, dengan adanya berbagai budaya dari luar yang ikut mewarnai
dan melekat dalam arsitektur Keraton Kasepuhan, menandakan bahwa telah terjadi
akulturasi budaya dalam Kesultanan Cirebon. Pandangan penulis sejalan dengan
teorinya Keesing bahwa akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul jika suatu
52
Jeremy Huang, Mengungkap Keberadaan dan Budaya Etnis Tionghoa Cirebon,
(Cirebon: Katalog Online Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati, 2006), h. 53. 53
David Lievander, Olivia, dan Kuo Chun-I, “Ritual Perayaan Imlek Etnis Tionghoa Di
Kota Toli-toli”. Century: Journal of Chinese Language, Literature and Culture, vol. 5, no.
1, 2017, h. 10-17. 54
Salim, “Memaknai Pengaplikasian Ornamen…,”, h. 50-65 55
Wawancara dengan Opan Safari (Filolog dan Budayawan Cirebon) pada tanggal 19
Juli 2020.
156
kelompok manusia dengan budaya-budaya tertentu bertemu dengan unsur-unsur
budaya asing tertentu, sehingga kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan
diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan identitas kebudayaan
masing-masing hilang.56
Dari bangunan Keraton Kasepuhan, penulis melihat beberapa hal. Pertama,
Bangunan mencerminkan bahwa Kesultanan Cirebon berbasiskan ajaran Islam.
Kedua, bangunannya mencerminkan terjadinya proses akulturasi yang baik,
dibuktikan dengan bangunan-bangunan yang ada di Keraton Kasepuhan maupun di
tempat bersejarah lainnya. Perwujudan budaya-budaya dari berbagai negara ada
disini, dan diposisikan di tempat-tempat tertentu. Dengan demikian, budaya Cirebon
memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan Islam sebagai agama utama dan
mayoritas dipeluk masyarakat Cirebon. Ini terlihat dari makna-makna filosofis dari
bangunan-bangunan yang ada dalam Siti Inggil. Bangunan Siti Inggil dibangun
pada tahun 1529 pada masa Syarif Hidayatullah.
Secara keseluruhan, di bagian dalam Siti Inggil terdapat lima bangunan tanpa
dinding, dan beratap sirap. Deretan depan dari barat ke timur, di antaranya adalah
bangunan Mande Malang Semirang, Mande Semar Tinandu, Mande Pandawa Lima,
Mande Pelinggihan (Pengiring), dan Mande Karesmen.
1. Mande Malang Semirang
Gambar 6. Mande Malang Semirang
Sumber: Dokumentasi Mukhoyyaroh, 2020
Bangunan Mande Malang Semirang merupakan bangunan utama yang berada
di bagian tengah Siti Inggil. Fungsi bangunan ini dikhususkan sebagai tempat duduk
Sultan Cirebon beserta para keluarga, utamanya dalam berbagai kegiatan seperti
upacara pelatihan dan pelaksanaan pengadilan di Alun-alun Sangkalabuana tepatnya
di sebelah utara Keraton Cirebon. Mande Malang Semirang ditopang oleh enam
tiang utama yang melambangkan rukun iman, dan jika dihitung keseluruhan
tiangnya berjumlah dua puluh yang melambangkan dua puluh sifat Allah.
Pelambangan rukun iman sebagaimana yang ada pada enam tiang utama
Mande Malang Semirang dalam kaitannya dengan Islam mengarah pada masalah
akidah. Sementara dalam Islam pembahasan mengenai akidah, salah satunya ialah
rukun iman yang enam, sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini:
56
F. M. Keesing, Culture Change: An Analysis and Bibliography of Anthropological
Sources to 1952, (New York: Stanford University Press, 1953), h. 1.
157
Dari Umar RA berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW bahwa: “...Maka
terangkanlah kepadaku tentang iman jawab Nabi, hendaklah engkau beriman
kepada Allah, kepada malaikat-Nya, kepada kitab kitab-Nya, kepada utusan
utusan-Nya, kepada hari kiamat, dan hendaklah engkau beriman kepada
Qodar yang baik dan yang buruk...”(HR. Muslim).
Kesadaran terhadap akidah (kepercayaan) artinya mempercayai sepenuh hati
terhadap keberadaan yang gaib merupakan suatu sikap jiwa yang diperoleh karena
pengetahuan yang berproses demikian rupa sehingga membentuk taat nilai atau
norma maupun prilaku seseorang.57
Sementara itu, dua puluh tiang penyanggah yang melambangkan dua puluh
sifat Allah. Menurut al-Asya'iroh, pembagian sifat terbagi menjadi tiga, di yaitu:
Pertama, Sifat Wajib adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah SWT yang
sesuai dengan keagungan-Nya. Sifat wajib ini ada dua puluh yang terbagi menjadi
empat kategori, yaitu: (1) Sifat nafsiyah (sifat yang menetapkan adanya Allah
SWT). Sifat ini hanya ada satu, yaitu sifat wujud (ada). Dalil bahwa Allah SWT
memiliki sifat wujud disebutkan dalam al-Qur‟an, yang artinya “Maha Suci Allah
yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga
padanya matahari dan bulan yang bercahaya” (QS. Al-Furqan 25:61). (2) Sifat
salbiyah adalah sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak dan tidak patut
bagi Allah SWT, sebab dzat dan sifat Allah SWT Maha Sempurna dan tidak
memiliki kekurangan. Adapun yang termasuk dalam sifat salbiyah ada 5 yaitu:
qidam (terdahulu), baqa (kekal), mukhalafatu lil hawadits (tidak serupa dengan
yang baharu/makhluk), qiyamuhu binafsiihi (berdiri sendiri), wahdaniyah (Maha
Esa). (3) Sifat ma'ani adalah sifat yang tetap ada pada dzat Allah yang menjelaskan
keaktifan dzat Allah. Yang termasuk ke dalam sifat ma'ani yaitu: hayyun (Maha
Hidup), qudrah (Maha Kuasa), iradah (Maha Berkehendak), ilmun (Maha
Mengetahui), Kalam (Maha Berfirman), Sama' (Maha Mendengar), bashar (Maha
Melihat). (4) Sifat ma'nawiyah yaitu sifat yang disandingkan dengan sifat ma'ani
atau sifat yang menjelaskan tentang sifat ma'ani. Jumlahnya ada 7 yaitu : kaunuhu
hayyan (dzat yang selalu berkeadaan Maha Hidup), kaunuhu qadiran (dzat yang
selalu berkeadaan Maha Kuasa), kaunuhu muridan (dzat yang selalu berkedaan
Maha Berkehendak), kaunuhu aliman (dzat yang selalu berkeadaan Maha
Mengetahui), kaunuhu sami'an (dzat yang selalu berkeadaan Maha Mendengar),
kaunuhu bashiran (dzat yang selalu berkeadaan Maha Melihat).
Kedua, sifat mustahil (sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah SWT yang
menunjukkan kekurangan-Nya). Sifat mustahil merupakan kebalikan dari sifat
wajib. Jumlahnya ada dua puluh, yaitu adam (tidak ada), huduts (baru), fana
(rusak/binasa), mumatsali lil hawaditsi (serupa dengan makhluknya), qiyamuhu
bighairihi (berdiri dengan yang lain), ta‟addud (lebih dari satu), ajzun (lemah),
karahah (tidak berkemauan), jahlun (bodoh), al maut (mati), as shamam (tuli), al
umyu (buta), al bukmu (bisu), kaunuhu ajzan (keadaan-Nya yang lemah), kaunuhu
mukrahan (keadaan-Nya terpaksa), kaunuh jahilan (keadaan-Nya yang bodoh),
kaunuhu mayyitan (keadaan-Nya yang mati), kaunuhu ashamman (kedaan-Nya
57
Ahmad Munawar Ismail, “Aqidah as a Basic Of Social Toleranca: The Malaysian
Experience”. International Journal of Islamic Thought, vol. 1, 2012, h. 1-7.
158
yang tuli), kaunuhu a'maa (keadaan-Nya yang buta), kaunuhu abkam (keadaan-Nya
yang bisu).
Ketiga, sifat jaiz adalah sifat yang mungkin boleh dimiliki dan boleh tidak
dimiliki oleh Allah SWT. Bahwa Allah SWT berbuat apa yang dikehendaki. Sifat
jaiz hanya ada satu yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu (Allah berwenang untuk
menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendak-Nya).
Sebagaimana firman Allah yang artinya“Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia
kehendaki dan memilihnya…”(QS. Al-Qashas 28: 68).
Sifat wajib bagi Allah sebagaiman di atas, sangat penting untuk diketahui oleh
setiap orang Islam. Kaitannya dengan Kesultanan Cirebon, memahami hal tersebut
adalah wajar sebab Kesultanan Cirebon merupakan salah salah Kerajaan Islam yang
pernah jaya di masanya. Tentu doktrin keagamaan juga diterapkan oleh pihak
kesultanan kepada masyarakatnya. Tidak hanya itu, semua bangunan yang ada di
dalam Keraton Kasepuhan Cirebon juga memiliki makna simbolik dan filosofis
dalam kaitannya dengan nilai-nilai Islam. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu
sosok pemimpin Kerajaan Islam Cirebon, yakni Sunan Gunung Jati, ia tidak hanya
sebagai pemimpin kerajaan tetapi juga sebagai orang yang mendakwahkan Islam
pada masyarakatnya.
Masyarakat Cirebon, merupakan komunitas masyarakat yang mewarisi nilai-
nilai luhur dari tokoh agama Islam di tanah Jawa, yakni Syarif Hidayatullah (1448-
1568) yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Peradaban Islam yang
disebarkan oleh Sunan Gunung Jati memberi kontribusi pada pembentukan cara
pandang dunia yang menekankan aspek teosentrikberkisar sekitar Tuhan,
daripada konsep peradaban Barat yang lebih menekankan pada aspek
antroposentrikberkisar pada manusia. Semuanya itu berasal dari warisan kearifan
lokal Sunan Gunung Jati yang terus dilestarikan di kalangan masyarakat Cirebon
hingga saat ini.
Melalui bangunan Mande Malang Semirang, penulis melihat bahwa Susuhunan
Jati sebenarnya ingin menegaskan bahwa Kesultanan Cirebon dibangun di atas
fondasi iman atau tauhid, dan khusus dua puluh tiang penyanggah bangunan Mande
Malang Semirang menyimbolkan sifat wajib bagi Allah. Dengan demikian, melalui
simbol tiang-tiang menunjukkan betapa Kesultanan Cirebon sarat dengan simbol-
simbol ketauhidan.
2. Mande Semar Tinandu
Gambar 7. Mande Semar Tinandu
Sumber: Dokumentasi Mukhoyyaroh, 2020
159
Bangunan Mande Semar Tinandu sebagaimana pada gambar di atas biasa
digunakan atau berfungsi sebagai tempat duduk penasehat kesultanan, penghulu
keraton dan kepala kaum Masjid Sang Cipta Rasa. Bangunan yang terletak di
sebelah barat laut dari Siti Inggil ini ditopang oleh dua tiang penyanggah yang
melambangkan dua kalimat syahadat. Tidak hanya sebatas lambang, tetapi setiap
tahunnya pihak keraton melangsungkan sebuah tradisi keagamaan yang dikenal
dengan nama panjang jimatdalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad
SAW, yang dalam tradisi masyarakat Jawa di Yogyakarta disebut sekaten. Jimat
(kang siji kang kudu dirumat)dalam konteks ini adalah syahadat.
Sementara dalam Islam, syahadat dapat diartikan sebagai pernyataan janji setia.
Syahadat berasal dari kata syahada yasyhadusyahādatan atau syuhūdan yang
berarti menghadiri, menyaksikan, mengetahui, memberikan kesaksian, bersumpah,
mengakui, dan mendatangkan. Oleh karena syahadat juga bisa berarti sumpah, maka
harus dipenuhi dan tidak bisa dilupakan, sebab salah satu syarat seseorang dianggap
Muslim adalah dengan membaca dua kalimat syahadat, yakni pernyataan atau
pengakuan bahwa Allah adalah Tuhannya dan Muhammad adalah utusan Allah.58
Keraton Kasepuhan sebagai Kesultanan Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai
dan aturan Islam juga memiliki pandangan yang demikian. Karena syahadat adalah
sumpah yang tidak boleh dilupakan, maka syahadat harus tetap diingat dengan jalan
terus mengikrarkannya. Peristiwa ini telah diabadikan di dalam al-Qur‟an surat Al
A‟raaf [7] ayat 172-173. Dua ayat ini mengungkap secara jelas bahwa terjadi
pengambilan sumpah atau bai‟at syahadat langsung di hadapan Allah. Sumpah setia
tersebut membawa manusia lahir dalam keadaan suci bagi keyakinan Muslim.
Abd al-Raḥmān dalam Durūs al-Fiqhiyyah menyebut bahwa istilah syahadat
adalah memantapkan hati (ber-iqtiqod), sesungguhnya Allah Esa, tidak ada sekutu
bagi-Nya dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah rasul dan utusan
Allah.59
Sementara Muhammad Nawawī Al-Jāwy menerangkan bahwa syahadat
adalah tiang Islam, atau fondasi agama Islam. Terkait dengan beberapa rukun Islam
setelahnya, dikatakan Al-Jawī adalah sebagai pelengkap dari bangunan Islam.
Dengan demikian, syahadat adalah syarat sah diterimanya amal seorang Muslim,
atau dengan kata lain, jika seseorang itu belum bersyahadat, rukun-rukun Islam
setelahnya itu akan sia-sia.60
Dengan demikian, setelah seseorang mengikrarkan syahadat, maka ia telah sah
untuk mengamalkan hukum Islam. Bagi setiap orang yang ingin masuk ke agama
Islam, maka harus memenuhi lima rukun syahadat sebagaimana yang telah
disebutkan. Sementara bagi keturunan Muslim, tidak memerlukan ikrar syahadat
seperti muallaf, meskipun seumur hidupnya tidak pernah mengikrarkan syahadat, ia
sudah menjadi mukallaf. Dalam konteks ini, syahadat seperti roh bagi tubuh, ia
58
Fakhruddin, “Eksistensi Syahadat dan Shalawat dalam Prespektif Tarekat Asy-
Syahadatain”. Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan, vol. 4, no. 2,
2018, h. 242-267. 59
Abd al-Raḥmān, Durūs al-Fiqhiyyah, (T.tp.: Maktabah Syekh Salim, t.th.), h. 3. 60
Muḥammad Nawawī Al-Jāwy, Riyāḍ al-Badī‟ah, (Semarang: Pustaka al-„Alawiyah,
t.th.), h. 3.
160
merupakan kehidupan bagi semua elemen Islam. Karena begitu pentingnya
syahadat dalam kepercayaan Islam, Said Hawwa mengatakan bahwa amal kebaikan
yang dilakukan seseorang tidak ada artinya tanpa syahadat.61
Syahadat yang
dilafalkan adalah syahadat tauhid lā ilāha illa Allah dan syahadat Rasul Muḥammad
rasūl Allah. Kedua kalimat ini dinamakan dua kalimat syahadat (syahadatain), dan
tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Dalam konteks masyarakat Cirebon, khususnya di Keraton Kasepuhan, untuk
menjaga agar dua kalimat syahadat ini tetap terpelihara di dalam masyarakat
Muslim, maka ada tradisi yang dikenal dengan panjang jimat. Prosesi adat atau
tradisi panjang jimat adalah refleksi dari sebuah proses kelahiran Nabi Muhammad
SAW dan merupakan acara puncak dari serangkaian kegiatan Maulud Nabi
Muhamad di Keraton Kasepuhan Cirebon. “Panjang” berarti sederetan iring-iringan
berbagai benda pusaka, dan “jimat” berarti siji kang kang kudu dirumat (satu yang
dihormati yaitu kalimat syahadat “lā ilāha illa Allah”). Jika digabungan dua kata
tersebut memiliki arti sederetan persiapan menyambut kelahiran nabi yang teguh
mengumandangkan kalimat syahadat kepada umat di dunia. Umumnya, tiap-tiap
upacara terdiri atas kombinasi beberapa macam unsur upacara seperti berkorban,
berdo‟a, bersaji makan bersama, berprosesi, semadi, dan sebagainya. Urutannya
telah ditentukan sebagai hasil kreasi para pendahulunya yang telah menjadi tradisi
di dalam masyarakat Cirebon.62
Oleh karena panjang jimat telah menjadi tradisi secara turun-temurun, maka
sepanjang hayat dalam pandangan masyarakat Cirebon, setiap orang Muslim harus
menjaga dan merawat jimat-nya yaitu syahadat. Artinya, akidah seorang Muslim
harus tetap dijaga dan jangan sampai lepas. Kalau diperhatikan ritual-ritual yang
berlangsug di dalam tradisi panjang jimat hampir mirip dengan upacara yang
lainnya, yang semuanya mengukuhkan homogenitas model Jawa yang orisinil.
Maka pada saat itu tampaklah raja melakukan miyos dalem (penampilan raja
kehadapan rakyatnya). Kemampuan raja mencapai kesatuan dimanfaatkan untuk
mendengarkan keabsahan keraton. Pada saat yang sama, seorang raja
menyampaikan berkahnya untuk kesejahteraan rakyatnya.63
Secara serentak,
upacara tradis panjang jimat di Cirebon dilangsungkan di empat tempat yang
menjadi peninggalan dari Syarif Hidayatullah, yakni di Keraton Kasepuhan,
Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan dan kompleks makam Syarif Hidayatullah
pendiri Kasultanan Cirebon atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Djati.
Dengan demikian, dua tiang penyanggah bangunan Mande Semar Tinandu
adalah simbol dua kalimat syahadat yang makna filosofisnya adalah bahwa
Kesultanan Cirebon sejak awal pendiriannya adalah kesultanan yang berlandaskan
pada Ketuhanan, dan memegang akidah islamiyyah. Karena kesultanan ini
berbasiskan pada ajaran-ajaran Islam, maka secara otomatis semua hal yang
61
Said Hawwa, Al-Islam, terj. Badul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press,
2004), h. 33-34. 62
A.B. Usman, dkk., Upacara Sekaten dalam Pendekatan Teologis: Merumuskan
Kembali Interkasi Islam-Jawa, (Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2004), h. 205. 63
Ismawati, “Budaya dan Kepercayaan Jawa Masa Pra-Islam”, dalam Darori Amin
(ed.), Islam dan Kebudayaan Jawa, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), h. 20-21.
161
berkaitan dengan kehidupan bernegara disandarkan pada ajaran Islam. Kemudian
secara teologis, dua tiang penyanggah Mande Semar Tinandu menekankan pada
keesaan Allah, dan keesaan Allah itu kemudian dijabarkan pemaknaannya lewat
sifat wajib bagi Allah.
3. Mande Pandawa Lima
Gambar 8. Mande Pandawa Lima
Sumber: Dokumentasi Mukhoyyaroh, 2020
Mande Pandawa Lima adalah bagunan yang difungsikan sebagai tempat duduk
para panglima dan pengawal pribadi Sultan Cirebon. Bangunan ini berada tepat di
sebelah kiri bangunan utama dengan ditopang oleh lima buah tiang penyangga yang
melambangkan rukun Islam. Keimanan seseorang akan terlihat dari pengamalan
rukun Islam. Iman atau akidah seseorang itu letaknya di hati. Kuat dan lemahnya
iman seseorang akan terlihat dari seberapa ia mampu mengamalkan rukun Islam
tersebut.
Rukun Islam merupakan sendi-sendi agama Islam, serta merupakan tonggak
yang harus didirikan setiap orang Muslim agar bisa selamat hidupnya di dunia dan
akhirat. Banyak nilai dan makna yang dikandung rukun Islam yang bisa diamalkan
sehingga manusia benar-benar bisa menjadi wakil Allah di muka bumi sebagaimana
yang Dia kehendaki, yakni manusia yang memiliki fitrah penghambaan kepada-
Nya dalam semua aspek.64
Ada beberapa hadis yang memuat adanya rukun Islam
sebagai pondasi agama Islam, salah satu di antaranya adalah hadis yang dimuat
dalam kitab Sahīh Bukhari. Rasulullah SAW. bersabda: “Islam itu ditegakkan atas
lima, persaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan
sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah (Syahadatain), mendirikan
shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan Ibadah Haji ke Baitullah dan puasa pada
bulan Ramadhon” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis di atas menjelaskan kepada kita semua bahwa Islam ditegakkan atas lima
perkara. Sebagai makhluk yang memiliki fitrah (potensi beragama), kelima perkara
atau rukun tersebut harus dijalankan. Nilai dan makna yang terkandung di dalamnya
harus diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana juga yang
64
Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Sahih al-Bukhari, juz I,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1981).
162
ditekankan pada masyarakat Cirebon, khususnya di Keraton Kasepuhan, sejak
kesultanan Islam ini dipimpin oleh Sultan Sunan Gunung Jati. Upaya menerapkan
nilai-nilai dan makna yang dikandung rukun Islam dalam menjalankan kehidupan
yang penuh dengan masalah ini merupakan bagian dari strategi bimbingan Sunan
Gunung Jati sebagai yang mendakwahkan Islam untuk membantu manusia,
khususnya bagi keluarga Keraton Kasepuhan, dan masyarakat Cirebon secara
umum untuk menemukan fitrahnya kembali sebagai khalifah dan hamba Allah di
muka bumi.
Rukun Islam merupakan tonggak agama yang mulia, sebagaimana Imam al-
Qurthubi mengatakan bahwa yang dimaksudkan, lima rukun (rukun Islam)
merupakan dasar-dasar agama Islam dan kaidah-kaidahnya, yang agama Islam
dibangun di atasnya, dan dengannya Islam tegak.65
Sementara Imam an-Nawawi
juga ikut mengomentari hadis tersebut dengan mengatakan bahwa sesungguhnya
hadis ini merupakan pokok yang besar di dalam mengenal Islam, dan agama Islam
bersandar di atas hadis ini, dan hadis ini mengumpulkan rukun-rukunnya.66
Selain
dua ulama tersebut, Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa al-Bukhari memasukkan
hadis ini ke dalam kitab al-Iman, untuk menandaskan bahwasanya Islam adalah
nama bagi pekerjaan dan bahwasanya Islam dan iman itu, terkadang adalah satu
maknanya.67
Bangunan Mande Pandawa Lima yang dilengkapi dengan lima tiang
penyanggah, selain menyimbolkan rukun Islam, juga memuat makna filosofis dan
urgensi yang dapat ditelusuri dari penjelasan masing-masing rukun yang ada dalam
rukun Islam, yakni syahadat, shalat, zakat, puasa, haji.
Pertama, syahadat. Syahadatain berisi syahadat tauhid dan syahadat rasul,
keduanya wajib diucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap jiwa dan
memahami makna yang terkandung didalamnya. Sementara dalam Syarah Hadits
Arba‟in an-Nawawi dijelaskan bahwa meninggalkan syahadatain hukumnya kafir
secara ijma‟, dan syahadat seorang Muslim tidaklah sah sehingga terkumpul
padanya tiga hal, yakni keyakinan hati, ucapan lisan dan menyampaikan kepada
orang lain.68
Inilah nilai akhlak yang terkandung dalam syahadatain, yaitu
pengikraran dengan segenap jiwa (rohani), dengan memahami isi kandungannya.
Dengan demikian, syahadatain dapat bermakna: 1) kunci sahnya keempat rukun
Islam;69
2) cerminan dari komitmen terhadap enam prinsip rukun iman,
mengandung unsur keyakinan (nilai akidah), sebuah kekuatan visi, yaitu memulai
65
Ibn Daqiq al-„Id, Syarah al-Arba‟in Hadisan al-Nawawiyah, (Kairo: Maktabah Turos
al-Islami, t.th.), h. 20. 66
Imam an-Nawawi, Hadits Arbain al-Nawawiyah, edisi terjemahan, (Surabaya: AW
Publisher, 2005). 67
M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Mutiara Hadis, cet. V, Jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang,
19780), h. 99. 68
Imam an-Nawawi, Syarah Hadits Arba‟in Imam Nawawi Penjelasan 40 Hadits Inti
Ajaran Islam, terj. Ibn Daqiq al-„Id, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013). 69
Hafizh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fatḥul-Bari Syarh Sahih
Bukhari, jilid 1. (Kairo: Dar al-Hadis, t.th.), h. 54.
163
dengan tujuan akhir, dan membulatkan tekad diri;70
3) salah satu pilar, sehingga jika
satu pilar roboh, yang lain ikut roboh;71
4) mengandung kalimat tauhid (mengesakan
Allah), dan meyakini kebenaran utusan Allah, yakni Rasulullah SAW.
Kedua, shalat. Shalat mengandung makna meningkatkan keharmonisan dalam
berhubungan dengan sesama manusia dan alam semesta, di samping meningkatkan
keyakinan hubungan dengan Allah. Shalat wajib ditekankan supaya dilaksanakan
secara berjamaah. Selain dilipatkan pahalanya sampai 27 derajat, shalat berjamaah
sebagaimana dikatakan Agus dapat menghilangkan diskriminasi antar sesama
manusia, membina persatuan, menampakkan rasa persamaan, kuatnya satu barisan,
kesatuan kalimat, dan berlatih taat kepada Allah dalam masalah-masalah yang
bersifat umum atau masalah sosial.72
Shalat adalah konsentrasi akal pikiran dan jiwa
yang diorientasikan kepada Allah semata, juga menimbulkan ketenangan hati dan
ketentraman batin bagi pelakunya sebagaimana dalam al-Qur‟an surat Al-Ma‟arij
[70] ayat 19-23. Selain dalam ayat tersebut, shalat juga merupakan pelatihan
mengekang nafsu syahwat, membersihkan jasmani dan rohani dari sifat-sifat dan
perilaku tercela serta perbuatan keji dan mungkar sebagaimana firman Allah dalam
surat Al-Ankabut [29] ayat 45.
Shalat juga dapat memperkokoh jiwa untuk bersosialisasi dan meningkatkan
hubungan yang kuat antara sesama umat Islam, seperti solidaritas sosial, kesatuan
pemikiran dan kelompok.73
Selain itu, urgensi dari shalat adalah bangunan Islam
yang paling agung di antara kelima bangunannya sesudah dua kalimat syahadat.
Posisi dalam agama seperti tempat kepala terhadap tubuh. Maka sebagaimana orang
yang tidak berkepala tidak bisa hidup, demikian halnya seorang yang tidak
mengerjakan shalat, berarti tidak beragama,74
sebab shalat merupakan kewajiban
yang pertama dalam Islam.75
Ketiga, zakat. Dari segi definisi zakat berarti “menyucikan” dan
“mengembangkan” jiwa dan harta benda bagi pelaku zakat, sedangkan secara istilah
zakat berarti kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya
dengan syarat-syarat tertentu76
sebagaimana juga yang dikatakan Al Asqalani
bahwa yang dimaksud dengan mengeluarkan zakat adalah mengeluarkan sebagian
dari harta dengan ketentuan tertentu.77
Sementara di dalam al-Qur‟an, Allah telah
70
A. G. Agustian, Rahasia Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ;
Emotional Spiritual Quotient Berdasarkan 1 Ihsan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam,
(Jakarta: Arga Wijaya, 2001), h. 262. 71
Ahmad al-Hambali Ibn Rajab, Jami‟ul-„Ulum wal Hikam, (Beirut: Darul Ma‟rifah,
1987). 72
Bustanuddin Agus, Al-Islam, Buku Pedoman Kuliah Mahasiswa untuk Mata Ajaran
Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 106. 73
Ahmad bin Salim Badwailan, Dahsyatnya Terapi Shalat, terj. Ubaidillah S. Akhyar,
(Jakarta: Nakhlah Pustaka, 2007), h. 24-25. 74
Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Nasehat-nasehat Agama dan Wasiat-wasiat
Keimanan, terj. Zaid H. Al-Hamid, cet. I, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2002), h. 96. 75
Abdul Aziz Salim Basyarahil, Shalat; Hikmah, Falsafah dan Urgensinya, (Jakarta:
Gema Insani Press, 1996), h. 11. 76
Agus, Al-Islam…, h. 111. 77
Al-Asqalani, Fatḥul-Bari Syarh Sahih Bukhari, jilid 1. (Kairo: Dar al-Hadis, t.th.)
164
menggabungkan antara shalat dan zakat sebagaimana dalam surat Al-Baqarah [2]
ayat 110.
Kalau dicermati lebih jauh, kewajiban zakat dalam al-Qur‟an selalu
digambarkan dengan kata “ātu”suatu kata yang dari akarnya dapat dibentuk
berbagai ragam kata dan mengandung lebih dari satu makna, antara lain istiqamah
bersikap jujur dan konsekuen, cepat, memudahkan jalan, dan pelaksanaan secara
sempurna, serta mengantar kepada seorang agung lagi bijaksana.78
Secara
sederhana, makna-makna tersebut dapat dijelaskan bahwa zakat dikeluarkan dengan
sikap istiqamah sehingga tidak terjadi kecurangan, baik dalam pemilihan,
pembagian, dan perhitungannya; bergegas dalam pengeluarannya atau tidak
menunda-nunda sampai waktunya berlalu; mempermudah jalan penerimaannya; dan
bagi mereka yang melakukan petunjuk-petunjuk ini adalah seorang yang agung lagi
bijaksana. Sehingga dalam konteks ini, kesucian jiwa dapat melahirkan ketenangan
batin, bukan hanya bagi penerima zakat, tetapi juga bagi pemberinya. Karena
kedengkian dan iri hati dapat tumbuh pada saat seseorang yang berkecukupan,
namun enggan mengulurkan bantuan. Kedengkian ini menurut Shihab dapat
melahirkan keresahan bagi kedua belah pihak.79
Dari penjelasan di atas, maka makna yang dikandung zakat berdampak pada
manusia (pemberi zakat) itu sendiri sebagai bagian dari pengembangan dan
peningkatan, serta fitrah beragama. Hal ini dikarenakan dengan mengeluarkan
zakat, jiwa dan harta dari pemberi zakat akan menjadi suci (fitrah) dan berkembang.
Iman menjadi meningkat, jiwa menjadi tenang, dan harta menjadi bertambah.
Keempat, puasa. Puasa dari segi bahasa berarti menahan, yakni menahan diri
dari yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenam matahari, sedangkan
yang membatalkannya ialah makan, minum, bersetubuh, dan sengaja mengeluarkan
mani atau muntah dan sebagainya.80
Dalam Islam, puasa dikenal dengan beberapa
jenis, yakni puasa wajib, sunat dan haram. Puasa wajib adalah pada bulan Ramadlan
dan puasa nażar. Apabila seseorang berhalangan puasa karena sakit, dalam
perjalanan, haid, dan nifas, wajib dibayar pada hari lain sebanyak hari yang tidak
dapat dipuasakannya. Puasa sunat ialah puasa di luar bulan Ramadlan yang
dianjurkan oleh al-Qur‟an dan hadis, seperti puasa enam hari bulan Syawal, puasa
Arafah (9 Zhulhijjah) bagi yang tidak sedang menunaikan ibadah haji, puasa hari
Asyura‟ (10 Muharram), memperbanyak puasa pada bulan Sya‟ban, puasa hari
Senin dan Kamis, dan puasa pada pertengahan bulan Qamariyah. Tetapi haram
berpuasa pada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, serta pada hari tasyrîq, yaitu
tanggal 11, 12, 13 Zhulhijjah.
Salah satu nilai yang dikandung dalam ibadah puasa adalah nilai akhlak, yakni
melatih kesabaran, sebab dengan sabar menahan hawa nafsu dari apa segala yang
membatalkannya, kita diharapkan menjadi insan yang bertakwa (muttaqīn),81
78
M. Quraish Shihab, Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan, cet. XXX,
(Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006), h. 192. 79
Shihab, Lentera Hati…, h. 193. 80
Agus, Al-Islam…, h. 114. 81
Ridwan Malik, Puasa Ulat: Merenungi Jejak Tuhan, Bercermin pada Nurani,
(Cibubur: PT. Variapop Group, 2006), h. 56.
165
sebagaimana Allah SWT dalam al-Qur‟an surat Al-Baqarah [2] ayat 183. Menjadi
insan bertakwa (muttaqīn), tergantung pada bagaimana kualitas puasa itu sendiri.
Maka tidak salah jika al-Ghazali sebagaimana dikutip Malik membagi tiga
tingkatan atau kualitas puasa, yaitu puasa orang awam, puasa orang khusus, dan
puasa super khusus (khawas al khawas). Semakin tinggi tingkat puasa kita, semakin
besar pengaruh puasa dalam merubah kualitas diri manusia yang menjalaninya
menjadi lebih baik dari sebelumnya.82
Merujuk pada konteks di atas, puasa termasuk syariat Islam yang dilaksanakan
berdasarkan keikhlasan, menjadi rahasia antara hamba dengan Tuhan dan tidak ada
yang mengetahuinya, kecuali Allah SWT. Oleh sebab itu, puasa memilliki pahala
yang agung dan balasan yang besar, karena ia adalah ibadah yang dapat
mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keridhaan-Nya. Dengan demikian,
melalui bangunan Mande Pandawa Lima yang merupakan simbol rukun Islam,
sultan ingin menegaskan bahwa kesultanan ini memadukan akidah dan Syariah
yang bersumber dari ajaran Islam.
Kelima, Haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan merupakan ibadah
pokok yang keempat yang disyariatkan setelah ketiga pokok ibadah sebelumnya,
yakni: sholat, puasa Ramadhan dan zakat. Ibadah haji merupakan salah satu sarana
komunikasi antara seorang hamba dengan Khaliknya. Ibadah ini pertama kali
disyariatkan pada tahun keenam hijrah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali
Imran [3] ayat 96-97.
Haji sebagai ibadah fisik dan ibadah rohani bertujuan agar manusia
memusatkan segala yang dimiliki hanya untuk Allah. Dengan bekal kesadaran akan
persamaan manusia dan kelemahannya di hadapan Allah maka para tamu Allah
harus menanggalkan atribut-atribut “kebesaran” dengan mengenakan pakaian ihram
yang sama dengan yang lainnya. Pada saat itu semua manusia dari golongan
manapun semuanya sama. Salah satu pelajaran berharga yang harus dipetik bahwa
manusia tidak layak sombong dengan pangkat, keilmuan dan harta yang
dimilikinya, karena di hadapan Allah semua sama, yang membedakan hanyalah
ketakwaannya.
4. Mande Pelinggihan (Pengiring)
Gambar 9. Mande Pelinggihan (Pengiring)
Sumber: Dokumentasi Mukhoyyaroh, 2020
82
Malik, Puasa Ulat: Merenungi…, h. 56.
166
Mande Pelinggihan (Pengiring) digunakan sebagai tempat duduk pengiring
atau pejabat kesultanan, termasuk para hakim dan jaksa ketika ada persidangan
yang dilakukan oleh pengadilan kesultanan. Bangunan ini ditopang oleh delapan
tiang, yakni empat tiang di bagian tengah dan empat tiang di masing-masing pojok
bangunan. Delapan tiang penyanggah tersebut, selain dijadikan sebagai tempat
duduk para pejabat kesultanan, juga memiliki makna simbolik dan makna filosofis.
Bangunan Mande Pelinggihan diperkuat oleh empat tiang penyanggah di
bagian tengahmenyimbolkan empat anasir penting yang ada di alam: tanah, air,
udara dan api. Tanah merupakan unsur utama dan penting dari ekosistem. Tanah
merupakan hasil bumi dan nikmat Allah SWT yang harus kita pelihara
keberadaannya dengan sebaik-baiknya sebagaimana dalam al-Qur‟an surat Al
A‟raaf [7] ayat 58 dan surat Al Mu‟min [40] ayat 67. Dengan demikian, melalui
simbol tanah, ada pesan agama yang ingin disampaikan bahwa manusia itu
diciptakan dari tanah, dan akan kembali ke tanah. Jadi, berhati hatilah dalam
menjalani kehidupan di dunia karena setiap perilaku manusia akan dimintai
pertanggung jawabannya di akhirat kelak. Manusia harus sadar bahwa hidupnya di
dunia untuk mencari pahala, amal kebaikan untuk bekal di akhirat.
Komponen lingkungan lainnya yang sangat vital bagi kehidupan makhluk
hidup adalah air. Manusia baru bisa merasakan betapa pentingnya air ketika
kebutuhan akan air sulit dipenuhi, atau ketika air menimbulkan masalah. Di sisi
lain, air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusiamulai dari keperluan air
minum, memasak, mencuci, irigasi, industri sampai pada penyediaan energi dan
rekreasi. Seluruh aktivitas manusia tidak bisa dilepaskan dari air, atau dengan kata
lain, makhluk hidup sangat tergantung pada ketersediaan air.
Di dalam Islam air sangat penting sebagai sarana ibadah. Ketika seorang
Muslim akan berwudhu untuk sholat dan mandi junub untuk mensucikan diri, maka
air dibutuhkan untuk bersuci. Hal tersebut sebagaimana dalam al-Qur‟an surat Al-
Maidah [5] ayat 6, yang menjelaskan posisi strategis air, serta fungsinya dalam tata
kehidupan alam, manusia dan lingkungannya. Misalnya tentang asal dan penopang
kehidupan, daur hidrologi, sarana transportasi, dan sebagainya, bahkan Allah
melukiskan surga sebagai kebun yang dialiri sungai-sungai di bawahnya. Allah
SWT juga pernah mengadzab umat-umat terdahulu yang ingkar dan melampaui
batas seperti umat nabi Nuh, Firaun, kaum Saba dan umat-umat lainnya, dengan air.
Hal tersebut mengisyaratkan bahwa air merupakan sesuatu yang vital dan
diperlukan, tetapi juga bisa menjadi sumber masalah dan bencana.83
Begitu
pentingnya air bagi kehidupan manusia, maka telah menjadi kewajiban kita bersama
untuk merawatnya.
Selain komponen tanah dan air, udara juga merupakan salah satu unsur penting
dimana seluruh isi alam semesta yang ada bergantung padanya. Udara memberikan
manfaat bagi kehidupan seluruh alam. Udara terbentuk dari beberapa gas yaitu:
Helium (He), Nitrogen (N), Oksigen (O2) dan Karbon Dioksida (CO2). Semua
makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernafas. Gas oksigen juga dibutuhkan
83
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang & Diklat Kementrian Agama
RI dengan LIPI, Air dalam Perspektif Al-Qur‟an dan Sains, (Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur‟an, 2011), h. 1-3.
167
untuk pembakaran makanan dalam tubuh makhluk hidup. Dari pembakaran tersebut
menghasilkan energi, yang mana energi itu dibutuhkan untuk melakukan segala
aktivitas manusia. Selain O2, CO2 juga berperan dalam proses pernapasan manusia.
Kebutuhan manusia akan oksigen per jam rata-rata berjumlah 53 liter. Sementara
oksigen yang dihasilkan oleh fotosintesis dedaunan (tanaman) agar dapat
memproduksi kebutuhan 53 liter oksigen harus dihasilkan oleh minimal 3000
lembar daun atau sekitar 4 tanaman yang masing-masing minimal memiliki 750
helai daun. Namun, fakta yang ada saat ini, manusia mulai malas menanam pohon.
Semua halamannya dibeton, dan sebagai akibatnya, disamping tidak ada resapan
air, juga kebutuhan oksigen tidak terpenuhi, sehingga kualitas udara semakin buruk,
bahkan yang lebih memprihatinkan lagi banyak hutan yang dibabat habis.
Dengan demikian, ada pesan dibalik empat tiang penyanggah di bagian tengah
bangunan Mande Pelinggihan yang ingin disampaikan kepada manusia bahwa
sebagai makhluk beragama, manusia wajib bersyukur atas nikmat udara yang Allah
berikan, serta bersama-sama menjaga keseimbangan alam dan tidak merusaknya.
Dan ini terkait dengan tugas utama manusia sebagai khalifah yaitu merawat,
memakmurkan dan memanfaatkan alam ini untuk kemaslahatan bersama.
Penebangan hutan secara liar, membuang limbah ke sungai, dan membakar hutan
hanya akan merusak alam dan membuat keseimbangan yang ada menjadi timpang.
Menjaga keseimbangan alam adalah tugas manusia sebab manusia adalah
bagian integral dari alam semesta. Itulah sebabnya manusia memiliki kedudukan
yang sederajat dan setara dengan alam, dan semua makhluk di alam ini. Kenyataan
ini harus mampu membangkitkan perasaan solider, perasaan sepenanggungan
dengan alam dan dengan sesama makhluk hidup lain. Sebagai khalifah juga
manusia mempunyai tanggungjawab moral terhadap alam semesta, baik terhadap
keberadaan ataupun kelestariannya.
Adapun simbol empat tiang yang lain di masing-masing pojok bangunan
Mande Pelinggihan melambangkan empat penjuruh atau arah mata angin, yakni
utara, selatan, barat dan timur. Makna filosofisnya adalah kemanapun manusia
menghadapkan pandangannya, sesungguhnya sedang menghadap Allahpemilik
Kerajaan timur dan barat, serta semua arah mata angin. Allah pemilik arah terbitnya
matahari dan tenggelamnya matahari, serta apa yang ada di antara keduanya
sebagaimana dalam al-Qur‟an surat Al-Baqarah [2] ayat 115. Ayat ini memberikan
pengertian kepada manusia bahwa seluruh penjuru adalah milik Allah, dan Allah
tidak memiliki tempat khusus. Milik Allah timur dan barat, serta arah terbitnya
cahaya dan segala apa yang berkaitan dengan yang terdapat di sana, juga arah
terbenamnya cahaya. Oleh karena itu, kemanapun manusia menghadap selama
dalam rangka melaksanakan apa yang diperintahkan, maka disitulah akan
menemukan wajah Allah.84
Melalui empat tiang tersebut, ada pesan yang ingin
disampaikan, yakni setiap Muslim di manapun berada harus selalu mengingat Allah
serta melaksanakan kewajibannya untuk sholat lima waktu dan lain sebagainya.
Selain itu, penulis melihat makna lain dari empat arah mata angin adalah
bahwa sejak awal Kesultanan Cirebon terbuka kepada siapapun dan dari manapun
arah datangnya untuk menjadi pejabat kesultanan. Artinya, sultan tidak selalu
84
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 289.
168
mengedepankan nepotisme untuk menentukan orang-orang untuk menjadi pejabat
kesultanan, melainkan ia mencari orang-orang yang cocok, dan yang datang dari
mana saja selama orang-orang tersebut memiliki kompetensi dan setia kepada
kesultananmereka yang difungsikan. Hal tersebut diperkuat dengan hadirnya
orang-orang atau para pejabat kesultanan yang datang dari luar daerah Cirebon,
terutama mereka yang diketahui adalah etnis Tionghoa.
5. Mande Karesmen
Gambar 10. Mande Karesmen
Sumber: Dokumentasi Mukhoyyaroh, 2020
Bangunan Mande Karesmen jumlah tiang penyanggahnya sama dengan Mande
Pelinggihan, hanya saja, fungsinya dijadikan sebagai tempat menaruh peralatan
kesenian seperti alat musik gamelan. Di Kesultanan Cirebon, tradisi menabuh
gamelan sekaten (gong sekati)85
dilakukan dua kali dalam setahun, khususnya pada
peringatan atau acara-acara keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Gamelan
juga biasa dipertunjukkan di alun-alun, yang disaksikan oleh sultan dan
keluarganya. Sekalipun arsitektur bangunan Mande Karesmen sebagaimana dalam
gambar nampak seperti bangunan Hindu, tetapi sesungguhnya bangunan ini sarat
dengan nilai-nilai Islam.
Sebagaima disebutkan di atas, jumlah tiang bangunan Mande Karesmen sama
dengan Mande Pelinggihan. Empat tiang di bagian tengah merupakan simbol empar
anasir penting dalam kehidupan yaitu tanah, air, udara dan api. Sementara empat
tiang bagian luar merupakan simbol arah mata angin dengan makna filosofis agar
mnusia dimanapun berada selalu mengingat Allah SWT. Allah pemilik segala arah,
tidak ada tempat yang lepas dari monitor Allah. Jadi, manusia harus mawas diri dan
menjaga perilakunya dimanapun berada karena Allah senantiasa mengawasi dan
inilah makna ihsan“Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah,
jika kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Dia yang melihatmu…”. Ihsan juga
adalah melakukan ibadah dengan khusyu‟, ikhlas dan yakin bahwa Allah senantiasa
mengawasi dan memerhatikan apa yang diperbuatnya. Sebagaimana dalam hadis
Rasulullah:
Dari Umar r.a. dia berkata: Ketika kami duduk-duduk disisi Rasulullah SAW
suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang
sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas
perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun di antara kami yang mengenalnya.
85
Gamelan Sekaten (Gong Sekati) adalah alat kesenian buatan abad ke-15.
169
Hingga kemudian dia duduk dihadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya
kepada lututnya (Rasulullah SAW) seraya berkata: “Ya Muhammad,
beritahukan aku tentang Islam ?”, maka bersabdalah Rasulullah SAW: “Islam
adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Ilah (Tuhan yang disembah) selain
Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan
shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika mampu”,
kemudian dia berkata: “anda benar”. Kami semua heran, dia yang bertanya dia
pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi: “Beritahu aku tentang
Iman”. Lalu beliau bersabda: “Engkau beriman kepada Allah, malaikat-
malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau
beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk”, kemudian dia berkata:
“anda benar”. Kemudian dia berkata lagi: “Beritahukan aku tentang ihsan”.
Lalu beliau bersabda: “Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-
akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka Dia melihat
engkau”. Kemudian dia berkata: “Beritahukan aku tentang hari kiamat (kapan
kejadiannya)”. Beliau bersabda: “Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang
bertanya”. Dia berkata: “Beritahu aku tentang tanda-tandanya”, beliau
bersabda: “Jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat
seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba,
(kemudian) berlomba-lomba meninggikan bangunannya”, kemudian orang itu
berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau (Rasulullah) bertanya:
“Tahukah engkau siapa yang bertanya?”. aku berkata: “Allah dan Rasul-Nya
lebih mengetahui”. Beliau bersabda: “Dia adalah Jibril yang datang kepada
kalian (bermaksud) mengajarkan agama kalian” (HR. Muslim).
Hadis di atas menjelaskan bahwa Islam dibangun di atas tiga landasan utama,
yaitu iman, Islam dan ihsan. Oleh karenanya, hendaknya seorang Muslim
memandang ihsan sebagai bagian dari akidah keislaman, dan tidak memandang
ihsan sebatas akhlak yang utama saja. Ihsan yang dipahami dengan benar akan
mampu membentuk manusia-manusia Muslim yang tidak hanya soleh secara
individual tetapi juga sosial. Aktualisasi ihsan akan membuat para pelaku bisnis
tidak hanya semakin dekat kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia.86
Mande Karesmen adalah bangunan tempat alat musik gamelan. Maknanya
adalah bahwa budaya Cirebon merupakan budaya yang disenangi, disukai dan
dinikmati oleh siapa saja. Budaya Cirebon menembus segala arah mata angin.
Setiap orang dari manapun asalnya bisa ikut menikmati alunan gamelan yang
sedang dimainkan. Musik gamelan ini disamping sebagai media hiburan, juga bisa
mengurangi kecemasan dan depresi. Dari hasil penelitian Yusli dan Nurullya
Rachma menemukan bahwa gamelan bisa menjadi alternatif perawatan atau terapi
untuk lansia yang menghadapi masalah kecemasan.87
86
M. Djakfar, “Corporate Social Responsibilty: Aktualisasi Ajaran Ihsan dalam
Bisnis”. Ulul Albab, vol 11, no. 1, 2010, h. 111-130. 87
Utami Dwi Yusli dan Nurullya Rachma, “Pengaruh Pemberian Terapi Musik
Gamelan Jawa Terhadap Tingkat Kecemasan Lansia”. Jurnal Perawat Indonesia, vol. 3, no
1, 2019, h. 72-78.; Lihat juga Rita Hadi W, “Pengaruh Intervensi Musik Gamelan Terhadap
170
Penulis melihat bahwa akulturasi budaya pada Keraton Kasepuhan Cirebon
terjadi karena dua hal. Pertama, lokasinya yang strategis menjadikan Cirebon
sebagai pusat perdagangan, tempat bertemunya berbagai suku, budaya dan agama
antar bangsa. Kedua, sikap terbuka dari Sultan Cirebon merupakan faktor terpenting
yang mengakibatkan masuknya berbagai pengaruh budaya pada bangunan dan
masyarakat, khususnya pada bangunan Kraton Kasepuhan Cirebon. Akulturasi
budaya pada bangunan Keraton Kasepuhan yaitu berasal dari Tiongkok, Hindu,
Budha, Jawa, Eropa, Islam dan Arab. Budaya Tionghoa dapat ditemukan pada
bangunan Dalem Agung Pakungwati, bangunan Siti Inggil termasuk bangunan
Mande Malang Semirang, Mande Semar Tinandu, Mande Pandawa Lima, Mande
Pelinggihan (Pengiring), dan Mande Karesmen, serta Kucung Kutagara Wadasan,
Pintu Buk Bacem.
6. Makam Astana Gunung Jati
Cirebon adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki banyak situs
peziarahan Islam, salah satu yang sangat terkenal adalah makam Sunan Gunung
Jati. Kompleks makam seluas 5 hektare yang telah berusia lebih dari enam abad itu
terdiri dari sembilan tingkat pintu utama, yakni pintu Lawang Gapura di tingkatan
pertama, pintu Lawang Krapyak, Lawang Pasujudan, Lawang Gedhe, Lawang
Jinem, Lawang Rararoga, Lawang Kaca, Lawang Bacem, dan Lawang Teratai di
puncak kesembilan. Para peziarah hanya dibolehkan berkunjung sampai bangsal
Pesambangan, depan pintu Lawang Gedhe, pada tingkatan pintu keempat.
Sementara pintu kelima sampai kesembilan terkunci rapat, dan hanya sesekali
dibuka khusus bagi anggota keluarga Keraton Cirebon, atau orang yang mendapat
izin khusus dari Keraton Kasepuhan Cirebon, atau pada acara-acara tertentu seperti
Gerebeg Idul Fitri dan Idul Adha, Maulud Nabi, dan pada malam Jumat Kliwon.
Gambar 11. Tangga Masuk ke Makam Sunan Gunung Jati
Sumber: Dokumentasi Mukhoyyaroh, 2020
Depresi Pada Lansia di Panti Wreda Harapan Ibu Semarang”. Home, vol. 1, no. 2, 2013, h.
135-140.
171
Untuk sampai ke makam Sunan Gunung Jati, setiap peziarah harus melewati
sembilan pintu. Sembilan pintu tersebut merupakan simbol dari sembilan wali.
Selain sebagai simbol dari sembilan wali, sembilan pintu untuk sampai ke makam
Sunan Gunung Jati juga merupakan simbol dari sembilan lubang pada tubuh
manusia yang diberikan Allah SWT. Adapun yang dimaksud dengan sembilan
lubang pada tubuh manusia, yakni dua lubang mata, dua lubang hidung, dua lubang
telinga, satu lubang mulut, satu lubang alat kelamin dan satu lubang anus, yang jika
dihitung keseluruhannya, berjumlah sembilan lubang. Kaitannya dengan panca
indera, sebenarnya telah disinggung dalam al-Qur‟an surat Al-Insan [76] ayat 2.
Ayat al-Qur‟ān di atas sesungguhnya ingin menjelaskan bahwa panca indera
manusia merupakan pemberian dari Allah SWT. yang harus dijaga dan difungsikan
dengan sebaik-baiknya, sebagaimana pula kemampuan manusia dalam
menggunakannya. Karena itulah, dalam konteks ini panca indera manusia akan
dimintai pertanggungjawaban di hari akhir nanti, sebagaimana dalam al-Qur‟an
surat Al-Isra‟ [17] ayat 36. Afirmasi ayat ini terkait dengan indera eksternal dan
internal88
manusia turut terlintas eksplisit, terbukti, muncul pula terma yang terkait
dengan fungsi indera, yakni kesaksian (syahadah/witnessing) akan adanya Allah
SWT, malaikat dan hari akhir yang berdimensi imani. Yang berkaitan dengan
perjanjian awal (mitsāq) manusia pada masa pra wujud, yang berupa kesaksian
bahwa Allah adalah Tuhan (…alastu birabbikum…), yang mana pada saat itu, ruh
manusia mampu bersaksi setelah mengenali Allah sebagai Tuhan melalui indera
internalnya.89
Selain beberapa ayat yang telah disebutkan, ada juga ayat al-Qur‟an
yang berisi peringatan bagi manusia agar menjaga pandangan, pendengaran, lisan,
maupun kemaluannya. Hal ini secara tegas diabadikan Allah dalam al-Qur‟an surat
Fushshilat [41] ayat 22. Menurut Thabataba‟I sebagaimana dikutip Shihab bahwa
ayat tersebut mengisyaratkan pengawasan Allah terhadap manusia pada setiap
waktu dan tempat. Di manapun dan kemanapun manusia, Allah senantiasa
bersamanya. Dalam segala kegiatannya, manusia senantiasa berada di bawah
teropong yang mengawasi dan menyaksikannya.90
Sementara dalam ayat yang lain Allah secara khusus memperingatkan manusia
agar menjaga lisannya dengan menjauhi ghibahmembicarakan orang lain yang
tidak ada di depan kita tentang sesuatu yang tidak disenangi dari orang yang
dibicrakan. Sekalipun keburukan itu benar disandang atau terjadi pada orang yang
sedang dibicarakan, hal tersebut tetap terlarang. Apalagi jika keburukan yang
dibicarakan itu tidak disandang oleh objek ghibah, maka perbuatan tersebut
termasuk buhtan (kebohongan besar) sebagaimana dalam al-Qur‟an surat Al-
Hujuraat [49] ayat 12.
88
Muhammad Taqiyuddin, “Panca Indera dalam Epistemologi Islam”. Tasfiyah: Jurnal
Pemikiran Islam, vol. 4, no. 1, 2020, h. 113-138. 89
S. M. N. Al-Attas, Islam, Secularism and The Philosophy of the Future, (Kuala
Lumpur: ISTAC, 1985), h. 45-46.; Lihat juga S. M. N. Al-Attas, The Intuition of Existence,
(Kuala Lumpur: ISTAC, 1990), h. 193-194. 90
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mișbah, vol. 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 398-
401.
172
Ayat di atas menggambarkan betapa buruknya menggunjing, bahkan
Thabathaba‟I dalam Shihab menjelaskan bahwa ghibah adalah bagian dari hal yang
merusak masyarakat. Dampak positif yang diharapkan dari terwujudnya masyarakat
bisa gagal dan berantakan karena ghibah. Masyarakat yang harmonis antar
anggotanya, yang dapat bergaul dengan penuh rasa aman dan damai sulit terwujud
hanya karena ghibah. Ghibah juga dapat melemahkan hubungan kemasyarakatan
seperti rayap yang menggerogoti anggota badan yang digunjing, sedikit demi sedikit
hingga berakhir pada kematian.91
Dengan kata lain, keselamatan seseorang
tergantung pada usahanya dalam menjaga lisannya. Tidak sedikit orang yang
tergelincir dan celaka hidupnya karena ulah lisannya sendiri. Perkataan yang baik
akan membawa keselamatan, dan sebaliknya perkataan yang buruk akan
mencelakakan dan menghancurkan. Oleh karena itu, manusia harus hati-hati
menggunakan lisannya, sebab perkataan yang tidak baik akan mendatangkan murka
Allah dan menghapus segala kebaikan yang ada pada pelaku ghibah.
Selain beberapa ayat al-Qur‟an di atas, hadis nabi memberikan kabar gembira
bagi mereka yang mampu menjaga lisan dan kemaluannya. Rasulullah SAW
bersabda: “Barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku (untuk menjaga) apa
yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka kuberikan kepadanya
jaminan masuk surga” (HR. Bukhari). Hadis ini menginformasikan kepada kita
bahwa akan datang bencana besar untuk menimpa seseorang yang tidak mampu
menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya (lisan dan
kemaluan). Sebaliknya, barang siapa mampu menjaga keduanya, berarti ia telah
mencegah terjadinya bencana besar dan menjauhkan diri dari berbagai macam
perbuatan maksiat, dan akan membuat seseorang selalu dalam naungan, rahmat dan
karunia Allah SWT. Lebih lanjut, Setiani mengatakan bahwa dorongan syahwat
yang tidak disalurkan melalui lembaga pernikahan, hanya akan menjerumuskan
manusia ke dalam lembah kehinaan.92
Penulis melihat bahwa makna dibalik simbol-simbol yang digunakan di dalam
Kesultanan Cirebon sebagai kesultanan Islam, khususnya pada makam Sunan
Gunung Jati yang terkait dengan panca indera erat kaitannya dengan makna yang
terdapat dalam Islam. Tidak heran, sejak dahulu hingga saat ini, secara turun
temurun dalam kepercayaan orang-orang Keraton Kasepuhan, sembilan lubang
yang ada pada manusia yang menurut analisa penulis erat kaitannya dengan panca
indera, harus dijaga kebersihannya karena semua itu merupakan pemberian dari
Allah SWT.
Dengan demikian, sembilan tangga yang juga merupakan simbol sembilan
lubang mengandung nilai-nilai religious. Sembilan lubang ini harus dijaga dan
dikendalikan untuk menjadi manusia ideal atau insan kamil yang beretika baik,
berhati bersih dan baik, serta dekat dengan sang Pencipta. Untuk sampai pada
ma‟rifat, manusia harus dapat memfungsikan sembilan lubang itu sebagaimana
petunjuk Allah SWT dan Rasulullah SAW. Manusia harus mampu mengendalikan,
91
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mișbah, vol. 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 256-
257. 92
Riris Eka Setiani, “Pendidikan Seks Bagi Anak : Perspektif Al-Qur‟an”. Yinyang,
vol. 12, no. 1, 2017, h. 57-84.
173
menjaga, dan memfungsikan sembilan lubang yang melekat dalam jasmani secara
benar dan konsekuen, sehingga tidak melanggar aturan agama, norma dan etika
pergaulan93
dalam bermasyarakat.
Sementara untuk naik atau masuk ke makam Sunan Gunung Jati ada aturanya
yang sudah menjadi ketetapan keraton. Masyarakat biasa hanya bisa sampai pada
pintu makam yang telah ditentukan. Ketetapan tersebut tidak hanya berlaku bagi
masyarakat biasa ketika berziarah, tetapi para pihak dari Kesultanan Cirebon pun
berziarah ke makam Sunan Gunung Jati, umumnya hanya dalam acara misalnya,
grebeg Syawal, seminggu setelah hari raya Idul Fitri, yang dipimpin langsung oleh
sultan keraton. Sementara yang membedakan dengan masyarakat umum, mereka
hanya boleh di pintu pasujudan, dimana tempat ini rutin diadakan tahlilan yakni
pada setiap malam Senin, malam Kamis dan malam Jumat.
Menurut Hafid ada dua alasan tidak diperkenankannya para peziarah atau
masyarakat umum masuk hingga ke makam Sunan Gunung Jati, yaitu: (1) Karena
masyarakat umum bukan bukan trah-nya Kanjeng Sunan Gunung Jati. (2) Dengan
pertimbangan bahwa di kompleks makam Sunan Gunung Jati telah tersimpan
banyak benda berharga, yang apabila semua masyarakat umum masuk,
dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan pada benda-benda berharga
didalamnya dan lain sebagainya.94
Meskipun, setiap manusia di mata Allah sama
kedudukannya, sehingga tidak ada pembatasan antara masyarakat biasa dangan
sultan, apalagi terhadap orang yang sudah meninggal. Namun, keturunannyalah
yang berhak untuk ziarah, di samping itu memang setiap raja sudah ada pekemnya
masing-masing, yang diatur oleh kesultanan secara turun temurun.
Gambar 12. Bagian Depan Tembok Makam Sunan Gunung Jati
Sumber: Dokumentasi Mukhoyyaroh, 2020
Hasan (juru kunci makam Sunan Gunung Jati) sebagaimana dalam Jaelani,
Setyawan dan Nursyamsudin menjelaskan bahwa yang menarik dari para peziarah
selain warga Muslim, banyak juga etnis Tionghoa yang berziarah ke makam Sunan
Gunung Jati. Di makam mereka berdoa, membakar hio, dan memberi santunan uang
kepada para pengemis di sekitar makam. Hal ini dapat dimaklumi karena salah satu
istri dari Sunan Gunung Djati yang bernama Ong Tien Nio adalah putri salah satu
Kaisar Dinasti Ming dari Tiongkok. Jadi, kedatangan etnis Tionghoa ke makam
93
Zaenuddin Bukhari, “Mistisisme Jawa: Studi Serat Sastra Gendhing Sultan Agung”.
(Disertasi IAIN Walisongo, 2012), h. 10. 94
Wawancara dengan Hafidz (Budayawan dan Pemandu Keraton Kasepuhan Cirebon),
pada tanggal 17 Juli 2020.
174
tersebut adalah untuk menziarahi leluhur mereka juga. Para peziarah Tionghoa
berdoa dan membakar dupa di bilik depan pintu Lawang Merdhu, sedangkan
peziarah pribumi berdoa di depan pintu Lawang Gedhe.95
Bagi masyarakat Cirebon, Sunan Gunung Jati adalah simbol religiusitas. Sunan
adalah wali Allah, yang merupakan status spiritual tertinggi umat manusia biasa,
kedua setelah para nabi. Mereka juga percaya bahwa wali Allah sempurna dan
memiliki hak istimewa dari Tuhan.96
Dengan posisi ini, orang Cirebon percaya
bahwa sunan adalah perantara antara para peziarah dan Tuhan. Keyakinan ini
berakar pada tradisi Islam yang menekankan bahwa wali Allah adalah yang terpilih,
perwakilan Allah di dunia material, dan memiliki pengetahuan yang langsung
berasal dari Tuhan.
Gambar 13. Tembok Depan Makam Astana Gunung Jati
Sumber: Dokumentasi Mukhoyyaroh, 2020
Selain itu, di Makam Astana Gunung Jati sebagaimana di Keraton Kasepuhan
dan keraton lainnya juga terdapat banyak ornamen-ornamen Tionghoa dalam bentuk
tempelan-tempelan keramik dan guci-guci dengan jumlah yang jauh lebih banyak.
Bahkan, di Makam Astana Gunung Jati ada sebuah bangunan yang disebut Gedung
Kong yang di dalamnya berisi keramik-keramik dari Dinasti Ming yang dibawa
oleh Puteri Ong Tien Nio ketika datang ke Cirebon, dan itu diamini oleh Prof. Wan
Ming ketika mengadakan kunjungan ke Makam Astana Gunung Jati sebagai bagian
dari acara Seminar Internasional Cheng Ho yang diadakan di Hotel Aston
Cirebon.97
Gambar-gambar yang ada di keramik juga sama dengan gambar-gambar
yang ada di Keraton Kasepuhan di antaranya; gambar naga, ikan, bunga dan
phoenix. Gambar naga misalnya, bagi masyarakat Tionghoa merupakan simbol
harapan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan,
kemakmuran, keberuntungan, kejayaan dan kebahagiaan. Naga juga merupakan
95
A. Jaelani, E. Setyawan dan Nursyamsudin, “Religi, Budaya Dan Ekonomi Kreatif:
Prospek dan Pengembangan Pariwisata Halal di Cirebon”. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian
Hukum Ekonomi Islam, vol. 2, no. 2, 2017, h. 101-122. 96
B. Sanusi, “Jum‟atan in the Graveyard: An Anthropological Study of Pilgrims in the
Grave of Sunan Gunung Jati Cirebon, West Java”. Journal of Indonesian Islam, vol. 4, no.
2, 2010, h. 317-340. 97
Penulis ikut serta dalam rombongan Prof. Wan Ming dalam kunjungannya ke Makam
Astana Gunung Jati pada tanggal 25 November 2018.
175
lambang kaisar yang dianggap sebagai “Putera Langit”. Maka, tidak heran jika
gambar naga melekat dengan simbol-simbol kekaisaran; pakaian, bangunan, dan
semua perlengkapan yang digunakannya. Sementara dalam kosmologi tradisional,
naga merupakan lambang hewan penjaga langit di bagian timur, mengatur hujan
dan musim semi. Secara keseluruhan lambang tersebut mengandung makna
kebaikan, kemuliaan, kebesaran, kemakmuran, kebahagiaan, kedamaian,
kehangatan, kelembutan, kehidupan dan hal-hal positif lainnya.98
Adapun gambar phoenix99
di Makam Astana Gunung Jati diduga kuat
mendapat pengaruh dari budaya Tionghoa di masa lalu. Berdasarkan wawancara
dengan Ajat,100
phoenix dalam mitologi Tiongkok merupakan simbol dari
kekuasaan, keindahan dan kemakmuran, sedangkan mitologi sendiri menurut Xinyu
dan Al-Muhsin dapat dimaknai sebagai kesatuan kesadaran primitif, yang
mengintegrasikan pemikiran, sains, sejarah, dan literatur orang primitif.101
Dalam
konteks itu, Connorton (ahli mitologi Amerika) percaya bahwa kebijaksanaan orang
primitif dan orang kuno tercermin dalam mitologi. Tetapi orang-orang modern tidak
tahu barangnya, secara membabi buta meninggalkan mitos-mitos ini. Jika mitos ini
bisa dipahami dengan benar, maka orang-orang modern dapat dibebaskan dari
tekanan spiritual.102
Sementara, Wickley (antropolog) percaya bahwa mitologi
penting untuk konsolidasi dan peningkatan budaya tradisional.103
B. Kereta Kencana Singa Barong
Kehidupan di Keraton Kasepuhan penuh dengan simbol-simbol yang memiliki
makna mistis, yang diberlakukan oleh raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan,
baik itu dalam arsitektur ataupun pranata yang lain.104
Simuh menjelaskan bahwa
kehidupan di keraton sarat dengan unsur-unsur mistis simbolik. Unsur-unsur mistis
98
Kustedja, “Makna Ikon Naga, Long, Elemen Utama Arsitektur Tradisional
Tionghoa”, h. 526-539. 99
Phoenix adalah makhluk mitologi yang disakralkan oleh masyarakat Tiongkok. Motif
phoenix ini hanya boleh digunakan sebagai motif hias permaisuri raja. Baik dalam
pakaiannya, penghias rambutnya, tusuk kondenya dan hiasan mewah lainnya. Binatang ini
digambarkan memiliki kepala seperti burung Pelikan, berleher seperti ular, berekor sisik
ikan, bermahkota burung merak, bertulang punggung mirip naga dan berkulit sekeras kura-
kura. Lihat Z. Tian, S. Ye, & H. Qian, “The Flying Dragon and the Dancing Phoenix:
Chinese Totem Myths”. In Myths of the Creation of Chinese, (Singapore: Springer, 2020), h.
43-74.; L. Xing, J. Zhang, H. Klein, A. Mayor, Y. Chen, H. Dai,... & S. Dong, “Dinosaur
Tracks, Myths and Buildings: The Jin Ji (Golden Chicken) Stones from Zizhou Area,
Northern Shaanxi, China”. Ichnos, vol. 22, no. 3-4, 2015, h. 227-234. 100
Wawancara dengan Ajat (Budayawan dan Pemandu Taman Air Sunyaragi). 101
Y. Xinyu & M. A. Al-Muhsin, “Comparative Study on Myth Between Chinese and
Arabic: Phoenix as An Example”. International Journal of Humanities, Philosophy and
Language, vol. 3, no. 10, 2020, h. 12-17. 102
Paul Connorton, How Does Society Remember, Nazi Biligo (translation),
(Shanghai: People's Publishing House, 2000). 103
John Wickley, Myths and Literature, Pan Guoqing, et al. (translation), (Shanghai:
Shanghai Literature and Art Publishing House, 1995). 104
Bukhari, “Mistisisme Jawa: Studi Serat Sastra Gendhing Sultan Agung”, h. 19-20.
176
simbolik itu bisa dilihat antara lain pada arsitektur bangunan, letak bangsal, ukiran
dan hiasan serta warna gedungnya yang semuanya memiliki nilai mistis.105
Salah satu peninggalan budaya Kesultanan Cirebon dalam bentuk fisik adalah
Kereta Kencana Singa Barong. Kereta kencana ini adalah kendaraan yang biasa
digunakan oleh raja dalam menjalankan tugas kenegaraan atau aktivitas sehari-
harinya. Kereta tersebut hingga saat ini menarik perhatian banyak pihak di samping
karena bernilai sejarah, juga bentuknya yang unik. Singa Barong adalah makhluk
hibriditas,106
yang merupakan hasil akulturasi budaya yang menghiasi
perkembangan kebudayaan dan seni hias di Cirebon. Lain halnya Kereta Kencana
Paksi Naga Liman yang dibuat pada tahun 1428 M oleh Pangeran Cakrabuana dan
Panembahan Losari, Kereta Kencana Singa Barong dibuat pada tahun 1649 M107
sebagai kereta Sunan Gunung Jati yang saat ini tidak lagi dipergunakan, dan hanya
dikeluarkan setiap 1 Syawal untuk dimandikan.
Benda-benda yang sekarang tersimpan di dalam keraton biasanya tidak hanya
memperlihatkan nilai artistik dan fungsional sebagai suatu produk seni-budaya,
tetapi di dalamnya juga mengandung apa yang disebut sebagai nilai-nilai simbolik
religio-magis.108
Munro mengatakan setiap bentuk erat kaitannya dan bahkan tidak
bisa dipisahkan dari konten yang ada di dalamnyamemuat isi material, gagasan,
spirit, makna dan pesan serta aspek psikologis individu atau masyarakat yang
menghasilkan dan memakainya.109
Bentuk dan konten pada akhirnya menjadi ciri
khas atau karakteristik sebuah objek seni, dan yang membedakannya dengan objek
seni lain.
Konon di dalam Singa Barong terdapat tiga makhluk mitologi, yaitu naga,
gajah dan buraqmenyatu dan menjelma menjadi sebuah makhluk. Masing-masing
simbol tersebut mengandung banyak makna. Ornamen yang berasal dari berbagai
kepercayaan, dan negara menunjukkan bahwa Kereta Kencana Singa Barong
merupakan wujud akulturasi budaya dalam bentuk ornamen serta merupakan
105
Simuh, Sufisme Jawa, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999), h. 121. 106
P. A. Hardwick, “Horsing around Melayu: Kuda kepang, Islamic piety, and identity
politics at play in Singapore‟s Malay community”. Journal of the Malaysian Branch of the
Royal Asiatic Society, vol. 87, no. 306, 2014, h. 1-19. 107Dewi Fatimah, Metode Dakwah: Syiar Islam Ala Masyarakat Nusantara Abad 9-15 M, Jurnal
Kajian Islam Interdisipliner, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 97-118.
108
A. Odewale, “An Archaeology of Struggle: Material Remnants of a Double
Consciousness in the American South and Danish Caribbean Communities”. Transforming
Anthropology, vol. 27, no. 2, 2019, h. 114-132.; E. Kurniadi, “Structuralism Approach:
Symbolism of Traditional Batik Pattern of Javanese Traditional Clothes In Surakarta”.
In 3rd International Conference on Creative Media, Design and Technology (REKA 2018),
(Atlantis Press, 2018), h. 75-79.; J. E. Made, “Sacrifice in African Traditional Religion:
Differential Faith Issues in Religions”. Journal of Religion and Human Relations, vol. 8, no.
1, 2016, h. 20-35. 109
T. Munro, Form and Style in the Arts: An Introduction to Aesthetic Morphology,
Cleveland: Press of Case Western Reserve University, 1970), h. v-vii.
177
manifestasi dari toleransi beragama dan wujud persahabatan antar negara.110
Hal
tersebut senada dengan apa yang dikatakan salah seorang pemandu keraton, Iman
Sugiman bahwa Kereta Kencana Singa Barong merupakan lambang persahabatan
Kesultanan Cirebon dengan tiga negara (Mesir, India dan Tiongkok).111
Penulis
melihat bahwa hal tersebut masih dapat diterima, sebab sejak dahulu, Cirebon
menjadi salah satu pelabuhan internasional, sehingga wajar jika masyarakat Cirebon
menjalin hubungan sosial dan perdagangan dengan para pedagang asing.
Gambar 14. Kereta Kencana Singa Barong
Sumber: Dokumentasi Mukhoyyaroh, 2020
Kereta Kencana Singa Barong di Keraton Kesepuhan merupakan lambang
penyatuan kekuatan yang dilambangkan dengan hewan-hewan (burung adalah
lambang dari dunia Islam Arab, naga adalah lambang keuletan, lincah dari
Tiongkok, gajah atau liman yang berasal dari India, yakni lambang kekuatan). Yani
dalam risetnya mengatakan Kereta Kencana Singa Barong sama maknanya dengan
Kereta Paksi Naga Liman yang berada di Keraton Kanoman yang mengandung
makna simbolik sebelum Islam, Hindu, Buddha. Menganut prinsip Tribuana di
dalam keserasian, yakni keserasian di antara dunia bawah (ular), dunia tengah
(gajah), dunia atas (burung). Jika tiga buana itu dikuasai akan diperoleh kekuasaan,
dan kekuasaan itu untuk dikendalikan dari keadaan yang kurang baik menuju
kepada yang lebih baik.112
Wujud Singa Barong sebagaimana pendapat lain mengatakan adalah konstruksi
kebudayaan Cirebon di masa silam yang terbentuk dari tiga kekuatan besar, yakni
kebudayaan Tionghoa, India dan Mesir. Sementara Sumino mengatakan ukiran
naga, Mega Mendung dan warna merah keemasan pada Kereta Kencana Singa
Barong merupakan ukiran-ukiran gaya Tiongkok, dan menunjukkan peran
masyarakat Tionghoa di Cirebon pada waktu itu, sedangkan belalai gajah yang
melilit senjata Trisula menunjukkan peran penting orang-orang Hindu-India.
Adapun dengan lambang buraq menunjukkan peran penting Islam dari Arab.113
110
W. Suardana & I. Fikriyyati, “Naga Liman Pencana Kencana Train Caruban Nagari's
Multicultural Symbols: Inculturalization of Nusantara Art in Cultural Arts
Education”. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, vol. 24, no. 2, 2020. 111
Wawancara dengan Iman Sugiman (Pemandu Keraton Kasepuhan Cirebon) pada
tanggal 09 Juli 2020. 112
Yani, “Pengaruh Islam Terhada…, h. 181-196. 113
Sumino, “Kereta Singa Barong di Keraton Kasepuhan Cirebon”. Corak: Jurnal Seni
Kriya, vol. 1, no. 1, 2012, h. 78-90.
178
Dengan demikian, pengaruh Hindu-Buddha, Tiongkok dan Islam menyatu dan
membentuk struktur budaya yang khas dan unik.114
Penulis melihat pengaruh dominan dalam ragam hias Singa Barong adalah seni
hias Tiongkok. Pembentukan ragam motif yang melekat pada Singa Barong sangat
dipengaruhi spirit maupun trend yang kemudian melahirkan motivasi pembentukan
ragam hias dalam periode tertentu. Lain halnya Kereta Kencana Paksi Naga Liman
yang banyak dipengaruhi spirit Hindu-Buddha, karena memang saat itu masa
peralihan dari Hindu-Buddha ke Islam. Meskipun harus diakui juga bahwa pada
masa pembuatan Kereta Kencana Singa Barong, pengaruh seni hias Hindu-Buddha
masih terasa, tetapi pengaruh seni hias Tiongkok meningkat tajam melalui
penerapan warna dan ornamen yang menjadi karakteristik seni hias Tiongkok.
Pengaruh seni hias Tiongkok begitu mendominasi dan mengalahkan seni-seni hias
lainnya termasuk seni hias Hindu-Buddha yang begitu kental mewarnai Kereta
Kencana Paksi Naga Liman. Hal itu disebabkan karena semua masyarakat Cirebon,
mulai dari raja sampai rakyatnya sangat terinspirasi oleh motif-motif unik yang
menempel di kain sutera, keramik dan benda-benda lainnya yang dibawa oleh Putri
Ong Tien.115
Kedatangan Puteri Ong Tien dari Tiongkok dengan barang-barang yang
dibawanya berupa keramik dan sutera yang dihiasi dengan berbagai macam motif
indah khas Tiongkok memberi pengaruh besar pada seni hias benda-benda yang
dihasilkan keraton. Contohnya adalah kereta di Kesultanan Cirebon, yaitu Kereta
Kencana Paksi Naga Liman dan Kereta Kencana Singa Barong.116
Kereta Kencana Singa Barong juga merupakan simbol perjalanan spiritual
manusia sebagaimana diketahui bahwa buraq merupakan kendaraan spiritual yang
dipercaya umat Islam digunakan Rasulullah ketika melakukan Isra Mi‟raj dari
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh (Sidratal
Muntaha) untuk menghadap Allah.117
Naga juga bagi etnis Tionghoa merupakan
simbol Kaisar yang dipercaya sebagai “Putera Langit”.118
Dalam mitologi
Tiongkok, naga merupakan binatang yang nafasnya menyerupai angin karena bisa
bergerak cepat, bahkan dianggap sebagai Dewa Langit. Sementara gajah, bagi orang
Hindu dianggap binatang yang disakralkan. Gajah tidak hanya dianggap sebagai
kendaraan Dewa Indra (Airavata), tetapi juga sebagai simbol kekuatan, kejantanan,
114
M. S. Andawari, S. Prabowo, & I. C. Angge, “Makna Simbolik Ornamen Gandhik
dan Wadidang Keris Saidi”. Jurnal Pendidikan Seni Rupa, vol. 3, no. 1, 2015, h. 113-118.;
G. Hodgson, “Keris Types and Terms”. Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic
Society, vol. 29, no. 4. 176, 1965, h. 68-90. 115
Sofiyawati, “Kajian Gaya Hias…, h. 304-324. 116
“Sultanskoets nooit meer als nieuw”, Nieuwsblad van het Noorden, Groningen, 29-
12-1993, h. 3. 117
Himatul Istiqomah dan Muhammad Ihsan Sholeh, “The Concept of Buraq in The
Events of Isra Mi‟raj: Literature and Physics Perspective”. AJIS: Academic Journal of
Islamic Studies, vol. 5, no. 1, 2020, h. 53-67.; Rizal Sapari, “Interaksi Simbolik dalam Tiga
Lukisan Kaca Karya Haryadi Suadi”. Jurnal Itenas Rekarupa, vol. 5, no. 2, 2019, h. 107-
114. 118
Kustedja, “Makna Ikon Naga, Long, Elemen Utama Arsitektur Tradisional
Tionghoa”, h. 526-539.
179
dan kebijaksanaan, serta simbol status sosial dan kesuburan. Gajah dipercaya bisa
mendatangkan hujan, sehingga dianggap sebagai Dewa Kesuburan yang dikenal
dengan sebutan Shri-Gaja.119
Motif Liman atau gajah pada Singa Barong terlihat pada bagian hidung atau
belalai. Motif Liman ini dipengaruhi oleh seni hias Hindu Buddha yang berasal dari
India. Liman adalah representasi dari sosok Ganesha. Dalam tradisi Hindu sosok
Ganesha dipercaya sebagai Dewa Keselamatan, Dewa Penolak Bala, juga Dewa
Penghalau Rintangan. Sosoknya sering dikaitkan dengan sosok pemimpin yang
gagah berani, ulet, dan mampu mematahkan barisan musuh namun berbudi luhur.
Dalam konsep kepemimpinan, motif Liman ini cenderung menekankan pada
kategori sosok pemimpin raja atau punggawa.120
Adapun Trisula yang ada dalam Singa Barong pada prinsipnya banyak
dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu. Dalam tradisi Hindu, Trisula merupakan
senjata Dewa Siwa. Senjata ini mempunyai tiga mata tombak yang berfungsi
sebagai senjata penyerangan, dan untuk pertahanan. Trisula adalah tombak yang
berbilah tiga. Jadi ada tombak yang berbilah tunggal, berbilah dua, berbilah tiga,
berbilah empat dan berbilah lima yang disebut Pancasula. Tombak merupakan salah
satu jenis senjata yang familiar dalam kehidupan manusia dimanapun berada.
Semua suku di Indonesia juga mengenal tombak. Awalnya tombak digunakan
sebagai alat berburu, kemudian digunakan sebagai senjata, sebagai benda upacara
serta menjadi pusaka yang turun temurun. Bentuk tombak juga mengalami
perkembangan dari masa ke masa, dari bentuk awal yang sederhana untuk berburu
kemudian digunakan sebagai senjata dalam berperang selain keris dan pedang.121
Senjata-senjata di atas merepresentasikan tiga sifat Dewa Siwa yaitu sebagai
pencipta, pemelihara dan pelebur. Kalau dikaitkan dalam kepemimpinan ketiga sifat
tersebut bermakna bahwa sosok pemimpin atau sultan harus memiliki cipta, rasa
dan karsa yang tajam. Bentuk Trisula ini juga bermakna bahwa seorang pemimpin
di samping memiliki sifat-sifat dalam kategori raja/punggawa juga harus memiliki
sifat resi.122
Dalam konsep Hindu, Trisula juga mengandung falsafah bahwa
masyarakat hendaknya terus mengolah batin spiritualnya untuk mencapai tajamnya
alam pikiran manusia dengan cara menghidupkan daya cipta, rasa dan karsa.123
Bagian badan dari Singa Barong biasa disebut umat Islam sebagai buraq
binatang sejenis kuda yang bersayap, dan berwajah cantik. Buraq dipercaya oleh
umat Islam sebagai kendaraan Rasulullah SAW ketika Isra Mi‟raj, bahkan ada yang
meyakini bahwa buraq juga yang membawa ruh Husain, cucu Rasulullah ke sisi
Allah setelah terbunuh di Padang Karbala. Di kalangan umat Islam mitologi buraq
selalu dikaitkan dengan pristiwa perjalanan Nabi menuju ke langit ketujuh pada saat
119
Prima Yustana, “Gajah dalam Terakota Majapahit”. Jurnal Dewa Ruci, vol. 7, no. 1,
2011, h. 102-114. 120
Sofiyawati, “Kajian Gaya Hias.., h. 304-324. 121
D. R. Indika, “Ingsun Titip Tajug Lan Fakir Miskin”, dalam “Pembangunan dengan
Berbasiskan Budaya dan Kearifan (Pengembalian Citra Keraton sebagai Pusat Kebudayaan
dan Ekonomi Cirebon”. ISEI Economic Review, vol. 2, no. 1, 2018, h. 1-7. 122
Sofiyawati, “Kajian Gaya Hias.., h. 304-324. 123
Sumino, “Kereta Singa Barong…, h. 78-90.
180
Isra Mi‟raj. Peristiwa ini sulit diterima oleh akal biasa, peristiwa ini hanya bisa
dipahami dengan keimanan, dan rukun iman yang keempat adalah beriman kepada
para Nabi.
Personifikasi kereta Singa Barong dengan buraq-nya mempunyai peran dalam
pembinaan dan pendidikan untuk membangun dan membentuk masyarakat Cirebon
yang religius. Karena buraq dipercaya oleh masyarakat Cirebon sebagai kendaraan
yang digunakan oleh Rasulullah dalam Isra Mi‟raj. Kepercayaan ini dipercaya
secara turun temurun bahkan oleh masyarakat muslim di daerah lainnya.
Kepercayaan ini menurut penulis perlu dilestarikan untuk memotivasi masyarakat
Cirebon agar terus membenahi dirinya agar menjadi manusia-manusia sholeh dan
terus meningkatkan keimanannya agar dapat bertemu dengan Tuhannya.
Perjumpaan antara hamba dan Tuhannya diisyaratkan dalam al-Qur‟an surat Al-
Ankabut [29] ayat 5.
Berjumpa dengan Tuhan tidak harus dipahami secara tekstual bahwa manusia
berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan adalah suasana batin
seorang hamba yang merasa begitu dekat dengan Tuhannya, sehingga tidak ada lagi
jarak antara dirinya dengan Tuhannya. Dengan kata lain, manusia benar-benar
merasakan kehadiran Tuhannya. Perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya
tidak bisa dibayangkan dalam bentuk fisik, tetapi perjumpaan secara rohani.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “An ta‟budallaha ka annaka tarohu, fa
inlam takun tarohu fainnahu yaroka” (Engkau menyembah Allah seakan-akan
engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak dapat melihat-Nya sesungguhnya Dia
melihatmu).124
Wujud perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya sangat
personal, setiap orang punya pengalaman spiritual yang berbeda-beda.
Kalau diperhatikan ornamen yang ada pada sayap Singa Barong adalah sayap
garuda. Garuda dalam keyakinan Hindu-Buddha dianggap sebagai sumber
kehidupan yang utama. Simbol garuda bermakna bahwa seorang pemimpin
hendaknya menjadi sosok yang dapat menerangi rakyat dan mensejahterakan
rakyatnya. Karena pada dasarnya rakyat sangat merindukan sosok pemimpin yang
bijaksana, adil, dan mengerti betul tentang aspirasi rakyatnya. Dalam konteks ini
garuda merupakan simbol keperkasaan dan perlindungan sekaligus juga
kebijaksaaan.125
Penulis melihat, ada beberapa motif asing, termasuk motif khas Tiongkok yang
ikut mewarnai ataupun mempergagah Kereta Kencana Singa Barong, di antaranya:
1. Motif Singa
Singa merupakan salah satu binatang yang banyak kita temui menghiasi
klenteng. Motif singa ini biasanya ditemukan di pintu masuk klenteng karena
dipercaya dapat menjaga, melindungi dan menjauhkan bangunan dan penghuni di
dalamnya dari segala marabahaya dan hal-hal yang buruk. Singa juga merupakan
simbol keagungan, kemuliaan, keberanian, dan kekuatan. Dalam kepercayaan
Tionghoa, singa juga dipercaya sebagai Dewa pelindung anak-anak. Para orang tua
percaya bahwa singa dapat melindungi anak-anak dari roh jahat dan hal-hal buruk
124
Imam Bukhari, Ṣahīḥ Bukhōrī Kitāb Tafsīr al-Qur‟ān Bab Surat Luqman Ayat 34,
vol. 6, (Beirūt: Dār Ibn Tuq al-Najāḥ, 1422 H.), h. 115. 125
Sofiyawati, “Kajian Gaya Hias.., h. 304-324.
181
lainnya. Mereka juga berharap anak-anak akan tumbuh sekuat singa. Jadi roh singa
dipercaya dapat memberikan perlindungan dari roh-roh jahat. Jika ditemukan ada
singa yang memangsa manusia, mereka percaya manusia yang dimangsa adalah
manusia yang berdosa dan patut dihukum.126
Digunakannya motif singa pada Kereta Kencana Singa Barong merupakan
representasi dari singa yang dikenal dalam masyarakat Tionghoa. Bagi masyarakat
Tionghoa, singa merupakan simbol penolak bala yang pada masa kini menjelma
menjadi seni pertunjukan Barongsai yang biasa dihadirkan pada hari-hari besar etnis
Tionghoa dan dipercaya mampu mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, kedamaian
dan kebahagiaan.127
Motif singa tersebut memperkuat persepsi adanya pengaruh
gaya seni Tiongkok dalam Kereta Kencana Singa Barong. Pendapat penulis
dilandasi oleh pemikiran bahwa secara historis, sejak kehadiran Puteri Ong Tien,
corak seni hias Tiongkok yang tergambar di hampir semua bangunan Keraton
Kasepuhan, termasuk jenis kain sutera mulai banyak diminati dan ditiru. Di
samping itu, argumentasi lain yang dikemukakan adalah bahwa pada Singa Barong
dilengkapi atribut kalung yang mirip dengan kalung yang dipakai Singa Tiongkok.
Kalung ini menandakan bahwa binatang tersebut dipelihara oleh manusia sehingga
sekalipun buas tetapi dapat dikendalikan. Dalam konteks itu, singa diidentikkan
dengan simbol keberanian, kekuatan, kewibawaan, kekuasaan dan kebangsawanan.
2. Motif Naga
Naga adalah makhluk mitologi yang dihormati dan disakralkan oleh
masyarakat Tionghoa. Sehingga tidak heran gambar naga mereka jadikan sebagai
salah satu simbol kebudayaan, dan sebagai sebuah bentuk penghormatan, mereka
menerapkannya di pakaian, bangunan, properti rumah tanggga, keramik dan
sebagainya. Naga sering digambarkan sebagai binatang mitologi yang memiliki
kepala singa, bergigi runcing seperti serigala dan bertanduk rusa. Tubuhnya
panjang seperti ular bersisik ikan, tetapi memiliki cakar mirip elang.128
Naga dalam
pandangan masyarakat Tionghoa dipahami sebagai lambang kesuburan atau
binatang pembawa berkah.129
Masyarakat Tionghoa dimanapun berada sangat
memegang teguh kepercayaan ini, sehingga bisa kita temukan beberapa lokasi atau
wilayah yang sekalipun banjir dan mahal tetap diminati oleh masyarakat Tionghoa
126
Mulyono dan Thamrin, “Makna Ragam Hias Binatang pada Klenteng Kwan Sing
Bio di Tuban”, h. 1-8. 127
M. Li, “Performing Chineseness: The Lion Dance in Newfoundland”. Asian
Ethnology, vol. 76, no. 2, 2017, h. 289-317.; C. McGuire, “The Rhythm of Combat:
Understanding the Role of Music in Performances of Traditional Chinese Martial Arts and
Lion Dance”. MUSICultures, vol. 42, no. 1, 2015, h. 2-23.; J. R. Chen & T. Y. Li,
“Rhythmic Character Animation: Interactive Chinese Lion Dance”. In SIGGRAPH
Sketches, 2005, h. 72. 128
N. Aubrey, “A Dwelling Place for Dragons: Wild Places in Mythology and
Folklore”. In The Psychology of Religion and Place, (Cham: Palgrave Macmillan, 2019), h.
145-166.; S. Z. Sheikh, “Persian Allegory of Chinoiserie Motifs-Dragon and Phoenix or
Simurgh”. International Journal of Multidisciplinary and Current Research, vol. 5, 2017. 129
Sumino, “Kereta Singa Barong…, h. 78-90.
182
untuk dijadikan tempat tinggal dan tempat usaha karena diangggap wilayahnya
berlokasi di kepala naga.
Di Keraton Kasepuhan Cirebon, naga memiliki dua versi, yakni bentuk naga
yang memakai mahkotamendapat pengaruh seni hias Hindu. Naga ini sering
disebut dengan naga Jawa, sedangkan naga Liong merupakan pengaruh seni hias
Tiongkok. Naga Tiongkok memiliki moncong seperti buaya dan tidak bermahkota.
Simbol naga Liong merupakan lambang kekuasaan, keagungan, kekuatan,
kegagahan dan keberuntungan. Simbol ini juga membawa pesan bahwa seorang
penguasa harus perduli terhadap rakyatnya dan orang-orang yang berada di
bawahnya. Perupaan naga pada Singa Barong tidak terlalu menunjukkan “sifat
penguasa” karena tidak banyak menggunakan atribut-atribut kekuasaan. Walau dari
segi rupa terlihat menyeramkan, namun pemaknaan penulis atas sosok naga pada
Singa Barong terlihat semacam ada pembauran, bisa jadi pembauran dalam arti
antara seorang raja dengan rakyatnya. Hal ini diperkuat dengan posisi Singa Barong
yang tunduk tengadah seperti hewan peliharaan yang akan jinak kepada
majikannya. Namun, dalam kondisi yang membahayakan, ia bisa menunjukkan
sosok angkara murkanya. Oleh karena itu, naga pada Singa Barong menunjukkan
sosok kategori Rama, yang dipercaya merupakan sosok pemimpin yang lebih
banyak berhubungan atau terlibat langsung dalam melayani dan menangani
masyarakat.130
Jenis naga pada Kereta Kencana Singa Barong sebagaimana disebutkan di atas,
terdiri dari naga kecil dan naga besar. Di bagian penutup atas kereta terdapat empat
naga kecil yang merupakan simbol empat penjuru mata angin, sedangkan dua naga
kecil di bagian depan melambangkan keseimbangan. Sementara naga besar yang
ada di kepala merupakan simbol seorang raja yang bermakna bahwa seorang
pemimpin harus mampu mengendalikan nafsu yang ada dalam raganya. Seorang
pemimpin tidak boleh memperturutkan hawa nafsunya ketika mengambil sebuah
keputusan, hendaknya menggunakan akal dan hati nuraninya dengan tetap
berpegang teguh pada al-Qur‟an dan hadis, sehingga setiap keputusan yang diambil
mendatangkan maslahat buat umat.131
Selain itu, seorang pemimpin juga harus bisa
bersikap adil dalam berbagai aspek kehidupan, tanpa pandang bulu. Hal tersebut
ditegaskan Allah dalam al-Qur‟an surat An-Nisaa‟ [4] ayat 58.
Selain naga besar pada Kereta Kencana Singa Barong yang melambangkan
sosok seorang raja yang bijaksana, adil serta mampu mengendalikan hawa
nafsunya, juga terdapat empat naga kecil yang mengandung makna bahwa Allah
ada dimana-dimana. Allah pemilik kerajaan Timur dan Barat. Di manapun seorang
130
Pada zaman Kerajaan Sunda dahulu berlaku sistem pemerintahan yang unik, yakni
dikenal dengan sebutan Tri-Tangtu. System pemerintahan ini terdiri dari raja/punggawa,
rama dan resi. Dengan demikian, dalam pemerintahan Sunda Kuno ada tiga lembaga yang
secara bersamaan memegang jabatan namun ketiganya memiliki hak dan kewajiban yang
berbeda. Lihat W. Widyonugrahanto, N. H. Lubis, D. Mahzuni, K. Sofianto, R. M. Mulyadi,
& U. A. Darsa, “The Politics of the Sundanese Kingdom Administration in Kawali-
Galuh”. Paramita: Historical Studies Journal, vol. 27, no. 1, 2017, h. 028-033. 131
Wawancara dengan Hafidz (Budayawan dan Pemandu Keraton Kasepuhan Cirebon),
pada tanggal 17 Juli 2020.
183
pemimpin berada, selalu dalam pengawasan Allah. Jadi seorang pemimpin harus
selalu menjaga sikap dan prilaku jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang
dilarang Allah karena kepemimpinannya kelak akan dimintai pertanggungjawaban
di hadapan Allah.132
Jika setiap pemimpin merasa diawasi Allah, tentu tidak ada
pemimpin yang berani melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam konteks
Indonesia sekarang ini, praktek-praktek tersebut sangat miris dengan banyaknya
pejabat negara yang tertangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena
kasus korupsi. Ini pentingnya iman, Islam dan ihsan harus dipahami dengan benar
dan diperkuat.
Adapun dua Naga kecil di bagian depan menurut Hafidz bermakna
keseimbangan yang juga dapat ditemui dalam Islam. Yusuf Qardhawi menjelaskan
bahwa Islam adalah wasatiyyah, yaitu sikap hidup pertengahan atau sikap seimbang
antara kehidupan material dan spiritual.133
Ini artinya sebagai seorang Muslim harus
dapat menyeimbangkan antara dua kutub kehidupan yaitu kehidupan material yang
bersifat duniawi dan kehidupan spiritual yang bersifat ukhrawi. Hal tersebut
sebagaimana dalam al-Qur‟an surat Al Qashash [28] ayat 77. Ayat ini menjelaskan
bahwa menjaga keseimbangan dalam hidup adalah sebuah kewajiban. Menanggapi
hal tersebut Ya‟qub mengatakan ada golongan yang berwawasan keduniaan belaka
dan menganggap akhirat tidak penting, ini penganut faham materialisme dan
sekulerisme, mereka tidak mau tahu tentang Tuhan dan agama serta tidak percaya
adanya hari pembalasan di hari kiamat.134
Dengan demikian, manusia harus mulai
mengumpulkan bekal sedemikian sebanyak untuk kehidupan di akhirat kelak.
Dalam pandangan masyarakat Cirebon, naga dianggap perwakilan lambang
dari dunia bawah. Naga kerap diidentikan dengan sifat yang rakus. Lewat simbol
naga ini manusia diingatkan untuk menghindari sifat-sifat rakus dan mengendalikan
hawa nafsu. Simbol naga ini bila dikaitkan dengan sosok seorang raja bermakna
bahwa masyarakat merindukan seorang raja yang mampu menahan dirinya dari
sifat-sifat rakus, tamak dan sebagainya. Seorang raja hendaknya menjadi pelindung,
teladan dan penganyom bagi rakyatnya.135
Seorang raja hendaknya selalu
memerhatikan dan mendengarkan keluhan rakyatnya. Seorang pemimpin juga harus
dapat mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Seorang
pemimpin dilarang bersikap otoriter kepada rakyatnya. Jika ada suatu masalah,
hendaknya dimusyarahkan untuk memperoleh kebaikan demi kepentingan bersama .
Nabi Muhammad SAW telah mempraktikkan prinsip musayawarah ini bersama
para sahabatnya setiap mengambil keputusan yang bersifat publik, walau Nabi
selalu dalam kontrol Allah. Bahkan tidak jarang Nabi mengambil keputusan
berdasarkan suara terbanyak, misalnya dalam peristiwa perang Uhud, ketika
menghadapi serbuan kaum musyrikin. Dengan demikian, salah satu kriteria
pemimpin yang baik dalam Islam adalah yang mampu mengakomodir pendapat
132
Wawancara dengan Hafidz (Budayawan dan Pemandu Keraton Kasepuhan Cirebon),
pada tanggal 17 Juli 2020. 133
Yusuf Qordhawi, Karakteristik Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 12. 134
Hamzah Ya'qub, Filsafat Agama: Titik Temu Akal dengan Wahyu, (Jakarta:
Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 62. 135
Sofiyawati, “Kajian Gaya Hias.., h. 304-324.
184
bawahannya (rakyat) alias tidak otoriter, sekalipun dalam kondisi tertentu seorang
pemimpin harus membuat keputusan secara mandiri136
sebagaimana dalam al-
Qur‟an surat Ali Imran [3] ayat 159.
Dalam Islam, fitrah manusia memiliki tiga komponen pokok yaitu kalbu, akal
dan nafs yang saling berinteraksi dan terwujud dalam bentuk kepribadian. Nafs ini
memiliki beberapa pengertian, yaitu nafs dalam arti luas berarti diri atau individu
dengan segala totalitasnya yang mencakup aspek jasmani dan rohan, sedangkan
dalam arti sempit berarti jiwa. Sementara nafs dalam arti bagian dari aspek
kejiwaan berupa nafsu yaitu keinginan atau kecenderungan dan hawa nafsu.137
Dilihat dari kecenderungannya, ada tiga macam nafs manusia dalam al-Qur‟an,
yaitu nafsu ammarah (QS. Yusuf: 53), nafsu lawwamah (QS. al-Qiyamah: 2) dan
nafsu muthmainnah (QS. ar-Ro‟du: 28).
Di dalam rongga dadanya, manusia memiliki dua hati tetapi yang berfungsi
hanya satu yakni hati nuranihati yang mendapat cahaya dari Allah dan hati
sanubarihawa nafsu yang gelap gulita dan inginnya menyimpang dari ajaran
Allah.138
Hawa nafsu atau nafsu amarah yaitu jiwa yang selalu mendorong
manusia untuk membangkang pada perintah Allah, manusia selalu mengarah
kepada keburukan, senang dan condong kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah,
serta senang mengikuti bujuk rayu setan. Sekalipun manusia memiliki
kecenderungan untuk berbuat keburukan, namun sesungguhnya pada awalnya
manusia berat dalam melaksakannya, karena pada dasarnya, secara fitrah manusia
itu cenderung beriman dan tunduk pada Allah sebagaimana dalam al-Qur‟an surat
Ar-Rum [30] ayat 30.
Sejak lahir manusia itu bersih, suci dan condong kepada hal-hal yang positif.
Kecenderungan manusia kepada hal-hal positif karena memang sejak di alam ruh,
manusia sudah mengakui ke-Esaan Allah dan tunduk kepada-Nya. Sehingga bisa
dikatakan bahwa kecenderungan manusia kepada hal-hal positif merupakan
aktualisasi fitra imannya yang sudah ada sejak lahir.139
Oleh karena pada dasarnya
fitrah manusia itu beriman, maka manusia akan selalu merindukan Tuhan, taat,
khusyu, tawakal dan tidak ingkar terutama jika sedang mengalami kegelisahan,
kesedihan dan kesulitan hidup.
Allah menciptakan manusia terdiri dari dua unsur, yakni unsur jasmani dan
unsur rohani (ruh ilahi). Unsur jasmani dan unsur rohani merupakan dua kutub yang
saling berlawanan. Maksudnya, bahwa unsur jasmani adalah bersifat fisik, statis,
akan mati dan letaknya di bawah, sedangkan unsur ruh ilahi (spirit of God) bersifat
136
Muhammad Harfin Zuhdi, “Konsep Kepemimpinan dalam Islam”. Akademika, vol.
19, no. 1, 2014, h. 35-57. 137
Anwar Sutoyo, Manusia dalam Perspektif Al-Qur‟an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2015), h. 120-122. 138
Munawar Rahmat, “Manusia Menurut Alquran”. Ta‟lim, vol. 10, no. 2, 2012, h. 105-
122. 139
G. I. Serour, “Islamic Perspectives in Human Reproduction”. Reproductive
Biomedicine Online, vol. 17, 2008, h. 34-38.
185
metafisik, dinamis, menghidupkan dan letaknya di atas.140
Menurut Shihab unsur
ruh ilahi ini tidak akan ditemukan pada iblis, jin dan hewan.141
Secara implisit
kutub-kutub tersebut menunjukkan bahwa dalam diri manusia ada dua
kemungkinan, yakni di satu sisi manusia dapat meraih derajat setinggi-tingginya
dengan mengarahkan dirinya menuju tingkat ruhani yang tinggi, dan di sisi yang
lain manusia dapat terjerumus pada derajat yang lebih rendah dengan dorongan
nafsu jasmaninya. Menurut penulis ada dua kecenderungan manusia untuk
melakukan perbuatan buruk yakni karena ingin menutupi kesalahannya agar tidak
diketahui orang lain dan manusia yang bersangkutan tidak ingin ada cahaya yang
menerangi perbuatannya.
Quthub mengatakan salah satu unsur yang membedakan manusia dengan
makhluk Allah yang lain adalah ruh, sebab sejak awal keberadaannya, ruh yang
membuat manusia menjadi unggul dibanding makhluk lain. Ruh inilah yang
kemudian dapat menghubungkan dan membuat manusia mampu berkomunikasi
dengan Tuhannya, serta mengangkat manusia dari alam materi yang interaksinya
menggunakan panca indera ke alam materi yang interaksinya menggunakan hati dan
akal. Selain itu, dengan ruh manusia mampu mengetahui rahasia yang tersembunyi
dari sesuatu yang tampak.142
Manusia adalah makhluk Allah yang sempurna karena ia mempunyai jasad
yang indah dan dilengkapi dengan ruh atau jiwa. Namun, label sebagai makhluk
utama dan ciptaan terbaik Allah itu akan turun derajatnya menjadi hewan, jika
manusia tidak menggunakan akal secara baik dan benar berbagai potensi pemberian
Allah yang sangat tinggi seperti pemikiran, kalbu, jiwa, raga, serta panca indera.
Hal tersebut ditegaskan Allah dalam al-Qur‟an surat Al A‟Raaf [7] ayat 179.
Quthub lebih lanjut menjelaskan bahwa fitrah setiap manusia senang dengan
lawan jenis, anak-anak, harta yang banyak (emas, perak, kuda pilihan, binatang
ternak, dan sawah/ladang). Semua merupakan sifat bawaan manusia yang tidak
dapat diingkari dan “dibunuh” karena menjadi bagian kebutuhan vital manusia agar
kehidupan menjadi kokoh, berkembang dan normal. Islam tidak mematikan semua
potensi itu, tetapi mengatur pemenuhannya atau penyalurannya dengan syariat
agama agar lebih terarah dan tidak menjerumuskan manusia ke jurang kenistaan.143
Motif-motif naga juga bisa ditemukan di bagian depan Kereta Kencana Singa
Barong berjumlah dua ekor dan empat ekor lainnya menjadi penopang singgasana
kereta. Namun naga-naga kecil ini merupakan naga Jawa. Simbol naga-naga kecil
itu bermakna bahwa harus ada sosok yang siap sedia untuk mengawasi dan
mengayomi rakyatnya.144
140
Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan
Kepribadiam Muslim, (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 69. 141
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, Juz I-
XXX, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 179. 142
Sayyid Quthub, Tafsir fi Zilali Qur‟an: Di Bawah Naungan Al-Qur‟an, (Jakarta:
Gema Insani, 2001), h. 137. 143
Quthub, Tafsir fi Zilali Qur‟an…, h. 41-43. 144
Sofiyawati, “Kajian Gaya Hias.., h. 304-324.
186
3. Motif Mega Mendung
Di Kereta Kencana Singa Barong juga ada motif Mega Mendungterletak di
bagian belakang maupun samping tempat duduk. Motif Mega Mendung merupakan
hasil adopsi dari seni Tiongkok. Mega Mendung adalah simbol awan dan mendung.
Bagi masyarakat Cirebon motif Mega Mendung bermakna harapan akan datangnya
hujan yang menyimbolkan kesuburan tanah pertanian bagi kehidupan masyarakat.
Datangnya hujan dianggap sebagai nikmat dan berkah tersendiri dari Allah SWT
yang Maha Pengasih kepada semua makhluk-Nya dan Maha Rahim kepada
makhluknya yang bertakwa. Motif Mega Mendung juga mengandung makna
filosofis bahwa seorang pemimpin harus sabar dan tidak cepat tersulut amarahnya
dalam menghadapi masyarakat. Seorang pemimpin hendaknya mampu mengontrol
amarahnya dan tidak gampang murka, juga harus mampu memberikan keteladanan
kepada rakyatnya. Dengan demikian, Mega Mendung secara filosofis bisa bermakna
harapan masyarakat akan hadirnya sosok pemimpin yang loyal, adil, bijaksana dan
mau terjun ke masyarakat untuk melihat dan mendengarkan langsung aspirasi
rakyatnya.145
Motif Mega Mendung juga bermakna bahwa setiap manusia hendaknya tidak
memperturutkan amarahnya dan harus mampu mengendalikan emosinya dalam
situasi dan kondisi apapun. Manusia harus tetap tenang dan damai hatinya sekalipun
dalam keadaan marah. Seperti awan yang muncul saat cuaca mendung, namun tetap
mampu mendinginkan keadaan sekitarnya. Selain itu, motif Mega Mendung juga
memiliki warna yang melambangkan sosok pemimpin. Awan biru merupakan
lambang atau melambangkan seorang pemimpin harus mampu melindungi
komunitas yang dipimpinnya. Di dalam motif asli Mega Mendung memuat tujuh
gradasi warna yang bermakna “langit memiliki tujuh lapisan, bumi tersusun dari
tujuh lapisan tanah, dan jumlah hari dalam seminggu (tujuh hari).146
Ragam hias Mega Mendung juga menggambarkan adanya mega-mega atau
awan-awan yang mengandung air menjelang turunnya hujanmerupakan simbol
dari harapan turunnya rahmat Allah berupa air hujan yang di dalamnya juga ada
tanda-tanda kehebatan Allah yang digambarkan dengan lidah petir atau kilat yang
terjadinya hanya sekejap mata (setralapan). Peristiwa lidah petir ini bermakna
bahwa hidup di dunia hanya sekejap atau sementara saja.147
Oleh karena itu,
manusia jangan terlena dengan keindahan dunia sehingga melupakan akhirat.
Karena kehidupan akhirat itu kekal, sementara kehidupan di dunia sifatnya
sementara.
4. Motif Wadasan
Kereta Kencana Singa Barong jika diperhatikan mengandung motif wadasan
yang mendapat pengaruh dari seni hias Tiongkok. Wadas berarti batu cadas atau
karangmengelilingi bagian belakang Singa Barong. Motif wadasan ini
perwujudannya menyerupai Mega Mendung yang berputar secara vertikal sehingga
145
Sofiyawati, “Kajian Gaya Hias.., h. 304-324. 146
M. Nurhidayat & Y. Herlambang, “Visual Analysis of Ornament Kereta Paksi Naga
Liman Cirebon”. Bandung Creative Movement Journal, vol. 4, no. 2, 2018. 147
Yani, “Pengaruh Islam Terhada…, h. 181-196.
187
seperti gunungan wadas. Sekalipun motif wadasan sekilas mirip dengan motif Mega
Mendung, namun sesungguhnya keduanya memiliki perbedaan. Menurut
pengamatan penulis, Mega Mendung berada di wilayah atas, sedangkan wadasan
berada di wilayah bawah. Di samping itu, pada wadasan biasanya ada tanaman yang
tumbuh menjalar. Wadasan ini bisa dijumpai di Guha Sunyaragi atau Taman Air
Sunyaragi,148
dan kompleks Tamansari Keraton Kasepuhan. Karena keindahannya,
motif wadasan menjadi salah satu ciri khas atau ikon Cirebon. Motif wadasan juga
mencerminkan adanya penempatan eksistensi raja sebagai penguasa jagad kecil dan
sebagai wakil Tuhan di dunia. Karena perannya yang begitu mulia, maka seorang
raja dituntut untuk terus meningkatkan kualitas spiritualnya agar mendapat
keberkahan dan bimbingan yang terus menerus dari Allah dalam memimpin
rakyatnya, sehingga kebijakannya akan selalu sesuai dengan aturan agama yang
ditentukan Tuhan bagi manusia. . Yani mengatakan motif wadasan melambangkan
kristalisasi keimanan seseorang.149
Seorang Muslim harus bertekad untuk terus
menjaga keimanannya agar tetap kuat dan mengamalkannya dalam kehidupan
sehari-hari. Perkara mengerjakan amal kebaikan telah disinggung dalam al-Qur‟an
surat An-Nahl [16] ayat 97. Ayat ini menegaskan bahwa dengan keimanan, seorang
mukmin akan memperoleh kebahagiaan, kenikmatan ketenangan dan kemantapan
hati dan jiwa, baik di dunia maupun akhirat. Dengan keimanan juga seorang
Muslim akan diselamatkan dari azab neraka dan kelak akan berjumpa dan
memandang wajah Allah SWT, dan inilak nikmat yang terbesar. Oleh karena itu,
wajib bagi seorang mukmin untuk memegang teguh keimanan, menjaga dan
merawatnya hingga kematian menjemputnya.
5. Motif Bunga Teratai
Dalam seni hias etnis Tionghoa, teratai melambangkan kesucian dan
kesempurnaan. Teratai tetap tumbuh bersih dan menawan hati walau tumbuh dalam
lumpur atau rawa-rawa. Bagi etnis Tionghoa terutama pengikut Buddha, teratai
memiliki tempat khusus di hati mereka. Selain bermakna kesucian dan keberhasilan,
teratai juga dipercaya merupakan tempat duduk Sang Buddha yang melambangkan
keagungan. Tempat ini digunakan sebagai penyembahan kepada Tuhan. Dengan
cara membakar hio hingga asapnya membumbung tinggi ke langit. Asap tersebut
diharapkan dapat membawa segala doa dan pengharapan yang dipanjatkan.150
Beberapa sumber menyebutkan bahwa motif bunga teratai mendapat pengaruh
dari gaya seni Tiongkok. Bagi masyarakat Tionghoa Cirebon, makna teratai juga
berkaitan dengan prinsip hukum sebab-akibat, atau dengan kata lain, apa yang
dipikirkan dan diperbuat oleh manusia, perkara baik maupun buruk pasti akan
mendapatkan balasannya di masa yang akan datang. Sementara kalau kita lihat
dalam Islam, konsep sebab-akibat terdapat dalam al-Qur‟an surat Al-Zalzalah [99]
ayat 7-8. Pada dasarnya setiap orang akan memetik apa yang ditanamnya.
Sementara dalam bahasa Mandarin, teratai disebut dengan he lian yang bermakna
perdamaian dan keberlanjutan. Teratai adalah bunga yang dapat hidup di air yang
148
D. Lombard, “Jardins à Java”. Arts Asiatiques, vol. 20, 1969, h. 135-183. 149
Yani, “Pengaruh Islam Terhadap…, h. 181-196. 150
Salim, “Memaknai Pengaplikasian Ornamen…, h. 50-65.
188
kotor tetapi bisa melindungi dirinya agar tetap bersih.151
Makna filosofisnya adalah
bahwa siapapun yang terus meningkatkan kualitas spiritualnya, maka akan
mencapai pencerahan spiritual dan tidak mudah terpengaruh pada kondisi
lingkungan yang tidak baik sebagaimana teratai yang tetap bersih dan tidak
terpengaruh dengan keadaan air kotor di sekelilingnya.
Sementara bagi masyarakat Cirebon, motif bunga teratai merupakan lambang
kebesaran dalam ketatanegaraan, juga merupakan lambang ruh atau spiritualitas
yang ada dalam diri manusia yang harus terus dijaga dan dirawat agar hidupnya
terus seimbang sebagaimana bunga teratai tidak akan bisa hidup tanpa adanya air di
bawahnya. Sementara dalam agama Hindu dan Buddha, bunga teratai merupakan
bunga yang dianggap suci dan bermakna religius. Simbol teratai ini bermakna
bahwa manusia harus terus mengembangkan sisi spiritualitasnya dan tidak
terpengaruh pada kesenangan duniawi.152
Singa Barong merupakan representasi dari perilaku sosial manusia yang
selanjutnya akan memengaruhi tatanan sosial berikutnya. Digagasnya Singa Barong
tentu tidak lepas dari jaringan sosial yang dibentuk manusia. Karena dalam
memproduksi objek atau budaya material, manusia tidak hanya bertujuan untuk
memuaskan diri sendiri atau orang lain, akan tetapi juga karena ingin mewujudkan
kebebasan dan kesadaran untuk berkarya dan mencipta sekaligus menunjukkan
bahwa manusia adalah makhluk yang produktif, baik secara individu maupun
kelompok.153
C. Batik Cirebon
Kajian tentang batik utamanya soal makna simbolik dan filosofis yang
terkandung di dalamnya perlu untuk digali lagi sebab rata-rata batik, khususnya di
Indonesia merupakan bagian dari warisan budaya yang tentu mempunyai nilai-nilai
tersendiri. Mengingat dalam konteks sekarang ini, batik telah menjadi bisnis di
kalangan pengusaha, dan karena pengaruh persaingan bisnis dalam industri batik
mereka tidak lagi mempertimbangkan nilai-nilai filosofis batik, kearifan lokal dan
budaya tradisional sebagai esensi utama dari seni batik Indonesia. Sehingga itu,
nilai-nilai filosofis dan unsur budaya lokal dalam batik cenderung menghilang.
Dengan kata lain, batik telah kehilangan jiwanya sebagai warisan budaya Indonesia
yang unik dan bernilai tinggi, bahkan menurut Budiono dan Vincent beberapa
pengusaha batik tulis telah mencampurkan batik mereka menjadi batik printing.
Beberapa produk batik printing yang diproduksi telah dilakukan secara asal-asalan
hanya demi memenuhi permintaan pasar.154
Sejak teknologi pencetakan ditemukan
pada tahun 1970, cetakan batik banyak tersedia di pasaran, namun memiliki harga
yang sangat murah dibandingkan dengan batik tulis.
Penelitian ini sebenarnya bukan membahas bagaimana batik ketika masuk
dalam dunia industri yang kemudian diperdagangkan, tetapi lebih kepada makna
151
Sofiyawati, “Kajian Gaya Hias.., h. 304-324. 152
Sofiyawati, “Kajian Gaya Hias.., h. 304-324. 153
Sumino, “Kereta Singa Barong…, h. 78-90. 154
G. Budiono & A. Vincent, “Batik Industry of Indonesia: The Rise, Fall and
Prospects”. Studies in Business & Economics, vol. 5, no. 3, 2010, h. 156-170.
189
simbolik dan folosofis dari batik itu sendiri. Contoh di atas, sengaja penulis
kemukakan di awal untuk menandai bahwa sesunggunya esensi batikkhususnya
makna simbolik dan filosofis di dalamnya, seiring berjalannya waktu mengalami
pergeseran. Sementara dalam konteks Indonesia, motif batik sesungguhnya
merupakan warisan budaya istana kerajaan atau kombinasi seni dan budaya lainnya
yang bernilai tinggi dan kerap menggambarkan makna simbolik dan filosofis
dibalik peristiwa yang terjadi di masa lampau, di samping batik juga sangat
potensial untuk diekspor hingga ke mancanegara.
Dalam konteks Indonesia, batik memang tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur
budaya yang sejatinya sudah ada sejak dahulu, salah satunya adalah batik di daerah
Sunda, Jawa Barat. Dilihat dari letak geografis, keberadaan batik di daerah Sunda
(yang dimaksud daerah Sunda berdasarkan wilayah administratif, adalah Jawa
Barat) dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni di sebelah utara Jawa Barat seperti
Cirebon, Indramayu, dan Kuningan, kemudian di sebelah selatan Jawa Barat, yakni
Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, dan Garut. Sehingga, batik di daerah Sunda (Jawa
Barat) terdiri dari batik dengan pengaruh batik pesisiran dan batik dengan pengaruh
batik priangan atau pedalaman.155
Batik pesisiran mengandung motif yang banyak
dipengaruhi oleh budaya-budaya asing (Tiongkok, Eropa, India, Persia, dan Arab),
yang memiliki warna-warna yang cerah, seperti motif Mega Mendung dari Cirebon.
Sementara pada batik priangan didominasi warna-warna lembut, gelap, seperti
hitam dan coklat, dengan komposisi warna terdiri dari sogan indigo (biru), hitam,
dan putih.
Batik sebagai salah satu warisan budaya bangsa Indonesia perlu untuk terus
dilestarikan di tengah globalisasi yang tentu saja bisa memengaruhi eksistensi batik
itu sendiri, terutama di tengah generasi muda yang cenderung senang dengan hal-
hal baru dari luar. Kalau batik ini tidak dilestarikan, maka suatu saat batik bisa
punah atau justru diklaim oleh negara lain. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO telah
mengukuhkan bahwa batik adalah Warisan Budaya Dunia Tak Benda yang berasal
dari Indonesia.156
Disebut demikian karena yang diwariskan adalah bukan benda
batiknya, namun prosesnya. Batik merupakan warisan kebudayaan tradisional atau
peninggalan nenek moyang, dan merupakan karya bangsa yang merefleksikan
sebuah produk seni serta memiliki nilai estetika bahkan filosofis yang tinggi.
Pada jaman dahulu para pengrajin batik dalam membatik tidak hanya
menciptakan sesuatu yang indah dipandang mata, tetapi juga mereka memberi arti
atau makna yang erat hubungannya dengan falsafah hidup yang diyakini. Ada
155
A. Joedawinata, “Unsur-unsur Pemandu dan Kontribusinya dalam Peristiwa
Perwujudan Sosok Artefak Tradisional dengan Indikasiindikasi Lokal yang Dikandung dan
Dipancarkannya (Studi dalam Konteks Keilmuan Seni Rupa, Kriya dan Desain dengan
Cirebon dan Artefak Kriya Anyaman Wadah-wadahan Sebagai Kasus)”. ITB, 2005. 156
I. Widiaty, L. S. Riza, & A. G. Abdullah, “A Preliminary Study on Augmented
Reality for Learning Local Wisdom of Indonesian Batik in Cocational Schools”. In 2015
International Conference on Innovation in Engineering and Vocational Education, (Atlantis
Press, 2015), h. 32-35.; A. Rahma, J. Jaenudin & A. Marifatullah, “Living a Multicultural
Lifestyle with Batik: Identity, Representation, Significance”. In International Conference on
Culture and Language in Southeast Asia (ICCLAS 2017), vol. 154, (Atlantis Press, 2017), h.
203-205
190
pesan-pesan dan harapan-harapan yang ingin disampaikan melalui motif-motif batik
yang diciptakan, agar membawa kebaikan dan kebahagiaan, khususnya bagi
pengguna batik. Motif batik yang diciptakan sangat dipengaruhi adat-istiadat,
kebudayaan dan agama.157
Misalnya pengaruh Islam terlihat pada tidak adanya
motif binatang dan lebih banyak motif tumbuh-tumbuhan dan unsur kaligrafi.158
Pengaruh adat terlihat pada batik Irian Jaya dengan ragam hias suku Asmat,159
dan
pengaruh Tionghoa dengan motif Mega Mendung pada batik Cirebon.160
Setiap batik memiliki latarbelakang, arti perlambangan atau makna simbolis
yang menjadi dasar penciptaan atau pembuatan, sehingga tatanan warna, pola
maupun motif pada batik tidak bisa sembarangan diubah, bahkan suatu budaya
diciptakan selalu tidak terlepas dari makna. Umumnya makna budaya tersebut
diciptakan dengan menggunakan simbol-simbol. Para sarjana yang banyak
mengkaji semiotika seperti Saussure,161
Kristeva,162
Yakin dan Totu,163
menyatakan
semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda (sign), berfungsinya tanda, dan
produksi makna. Tanda tidak hanya berbentuk sebuah benda, misalnya, dalam
kehidupan manusia, tanda selalu menyampaikan suatu informasi sehingga
mempunyai sifat komunikatif. Merujuk teori Pierce sebagaimana dalam karya-karya
157
K. Parmono, “Simbolisme Batik Tradisional”. Jurnal Filsafat, vol. 1, no. 1, 1995, h.
28-35. 158
Salah satu unsur kaligrafi bisa ditemukan dalam Lukisan Kaca Kusdono Cirebon,
yang diberi nama “Kaligrafi Semar” dan menggunakan kaligrafi Arab. Penggunaan Semar
sebagai objek karena Semar dalam wayang dikenal sebagai orang yang selalu berbuat baik,
menjaga kebenaran dan selalu taat pada ajaran Tuhan. Seni lukis “Kaligrafi Semar”
merupakan perpaduan kekuatan moral dan teologis yaitu pencitraan visual dalam bentuk
wayang dan kaligrafi sebagai ekspresi estetika non figuratif. Lukisan kaca Cirebon
“Kaligrafi Semar” disebut kaligrafi figural karena memadukan motif figural dengan elemen
kaligrafi melalui berbagai cara dan gaya. Lukisan Kaca Kusdono Cirebon menggunakan
motif Mega Mendung dan wadasan yang dikenal dengan motif batik Cirebon yang warnanya
menggunakan warna pantai karena letak geografis Cirebon yang dekat dengan pantai. Lihat
Y. Rukiah, “Visual Elements of Semar Calligraphy” on Cirebon Glass Painting of
Kusdono‟s Work”. In International and Interdisciplinary Conference on Arts Creation and
Studies, vol. 1, 2019, h. 43-47. 159
M. C. Howard, “Dress and ethnic identity in Irian Jaya”. Journal of Social Issues in
Southeast Asia, 2000, h. 1-29.; A. K. Hermkens, “Gendered Objects: Embodiments of
Colonial Collecting in Dutch New Guinea”. The Journal of Pacific History, vol. 42, no. 1,
2007, h. 1-20. 160
M. T. Riyanti & M. Rouselyn, “The Influence of Art Motif Batik Mega Mendung
Cirebon to Fesyen in Jakarta”. International Journal of Research of Granthaalayah, vol. 6,
no. 3, 2018, h. 107-125.; B. Sudardi, “The Reflection of Socio-Cultural Change in Batik
Motifs”. In 2018 3rd International Conference on Education, Sports, Arts and Management
Engineering (ICESAME 2018), vol. 231, (Atlantis Press, 2018), h. 150-152. 161
F. de Saussure, “Course in General Linguistics”. In Literary Theory, An Anthology,
by J. Rivkin & M. Ryan (eds.), (UK: Blackwell Publishing Ltd., 2004), h. 59-71. 162
J. Kristeva, Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art, (New
York: Columbia University Press, 1980), h. 31. 163
H. S. M. Yakin & A. Totu, “The Semiotic Perspectives of Peirce and Saussure: A
Brief Comparative Study”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 155, 2014, h. 4-8.
191
para sarjana seperti Dewey,164
Zeman,165
dan Houser166
bahwa tanda-tanda dalam
gambar dapat digolongkan ke dalam ikon, indeks dan simbol. Ikon adalah tanda
yang mirip dengan objek yang diwakilinya, atau tanda yang memiliki ciri-ciri yang
sama dengan apa yang dimaksudkan. Sementara indeks merupakan tanda yang
memilik hubungan sebab-akibat (kausalitas) dengan apa yang diwakilinya atau
disebut juga tanda sebagai bukti. Adapun yang dimaksud dengan simbol adalah
tanda berdasarkan konvensi, peraturan, atau perjanjian yang disepakati bersama.
Simbol baru dapat dipahami jika seseorang sudah mengerti arti yang telah
disepakati sebelumnya.
Makna simbolis yang terkandung dalam tiap motif batik di berbagai daerah
biasanya diartikan secara kultural menurut keyakinan, kebiasaan atau tradisi, serta
cara hidup dari masyarakatnya yang sampai sekarang tetap bertahan. Dalam
membuat sebuah motif batik, pengrajin akan menggunakan dasar-dasar yang
diyakini masyarakat untuk dijadikan sebuah makna. Dengan kata lain, masing-
masing motif batik ditafsirkan sesuai dengan makna yang ada di masyarakat.
Pemahaman terhadap simbol dapat diidentifikasi sebagai kata benda, kata kerja dan
kata sifat. Simbol sebagai kata benda dapat berupa barang, obyek, tindakan dan hal-
hal konkrit lain. Simbol sebagai kata kerja dapat berfungsi untuk menggambarkan,
menyelubungi, mengartikan, meperlihatkan atau menunjukan, memanipulasi, dan
menandai. Sementara simbol sebagai kata sifat berarti sesuatu yang lebih besar,
lebih bermakna, lebih bernilai, sebuah kepercayaan, dan prestasi. Adapun fungsi
simbol digunakan untuk menjembatani obyek nyata dengan hal-hal abstrak yang
maknanya melebihi dari makna hal yang tampak. Dalam konteks ini, Smiraglia
berpendapat bahwa simbol adalah kreasi manusia untuk mengejawantahkan
ekspresi dan gejala-gejala alam dengan bentuk-bentuk bermakna.167
Artinya, simbol
dapat dipahami dan disetujui oleh masyarakat tertentu.
Bagi orang Jawa, busana itu memiliki makna yang dalam “ajining diri
gumantung ono ing lati, ajining jiwo gumantung ono ing busano” (harga diri
terletak dari kualitas bicara seseorang demikian juga penampilan dan cara
berbusana akan memberi nilai terhadap kualitas jiwa seseorang). Busana adalah
cermin identitas seseorang, watak, kondisi sosial ekonomi pemakainya, juga
menunjukkan moral dan budaya suatu bangsa.168
Begitu juga bagi masyarakat
Cirebon, mereka memahami busana selain sebagai alat untuk melindungi diri juga
bernilai keindahan dan kesopanan.
Batik Cirebon sampai sekarang masih diproduksi dan dikembangkan oleh para
pengusaha Muslim dan para santri di Desa Trusmi, tidak heran jika masyarakat
164
J. Dewey, “Peirce's Theory of Linguistic Signs, Thought, and Meaning”. The
Journal of Philosophy, vol. 43, no. 4, 1964, h. 85-95. 165
J. Zeman, “Peirce‟s Theory of Signs”. A Perfusion of Signs, 1977, h. 22-39. 166
N. Houser, “Toward a Peircean Semiotic Theory of Learning”. The American
Journal of Semiotics, vol. 5 no. 2, 2008, h. 251-274. 167
R. P. Smiraglia, “Works as Signs, Symbols, and Canons: The Epistemology of the
Work”. Ko Knowledge Organization, vol. 28, no. 4, 2001, h. 192-202. 168
A. Nursalim & H. Sulastianto “Dekonstruksi Motif Batik Keraton Cirebon:
Pengaruh Ragam Hias Keraton pada Motif Batik Cirebon”. Jurnal Penelitian
Pendidikan, vol. 15, no. 1, 2016, h. 27-40.
192
umum lebih mengenal batik Cirebon ini dengan batik Trusmi. Ornamen batik
Cirebon memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ornamen batik dari
daerah lainnya. Ornamen batik Cirebon dipengaruhi oleh faktor internal dan
eksternal yaitu adanya budaya-budaya yang mengelilinganya. Ornamen sangat
berpengaruh pada maju mundurnya batik, artinya ornamen yang bagus dan unik
tentu akan lebih diminati dan dipakai oleh masyarakat.
Ornamen memberi hiasan pada bidang kosong menjadi berisi hiasan.169
Nenek
moyang bangsa Indonesia sejak lama sudah memiliki keahlian membuat ornamen.
Hal ini bisa dibuktikan pada pecahan gerabah dari zaman neolitikum berupa goresan
sederhana berbentuk geometris. Pada masa pra sejarah, ornamen berfungsi sebagai
media untuk melampiaskan hasrat, pengabdian, persembahan, penghormatan dan
kebaktian terhadap nenek moyang atau Dewa yang dihormati. Dengan kata lain,
ornamen memiliki fungsi ganda yaitu fungsi hias dan simbolik.170
Ornamen adalah
hiasan yang dibuat dengan digambarkan, dipahat, maupun dicetak untuk
meningkatkan kualitas dan nilai suatu benda atau karya seni. Ornamen sering
dihubungkan dengan corak dan ragam hias yang ada. Sementara simbol atau
lambang adalah tanda yang menyatakan sesuatu itu mengandung maksud tertentu.171
Di Jawa Barat sebenarnya ada empat tempat sentra batik, yakni daerah
Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, dan Garut. Namun, di antara keempat sentra
batik tersebut, Cirebon tergolong sebagai sentra batik tertua dan banyak
memberikan pengaruh pada perkembangan batik di daerah lain, terutama daerah-
daerah berdekatan di Jawa Barat, dan daerah Jawa pada umumnya. Dalam konteks
ini, Cirebon yang dahulunya sebagai kota pelabuhan merupakan tempat akulturasi
budaya dari berbagai suku dan bangsa. Misalnya, motif wadasan dan Mega
Mendung yang merupakan ikon batik Cirebon merupakan hasil akulturasi dengan
budaya Tiongkok. Gambar awan pada Mega Mendung merupakan pengaruh
oriental yang biasa ada di keramik-keramik asal Tiongkok, begitu pula dengan
warna cerahnya yang membedakannya dari batik Yogya, batik Solo172
dan
sebagainya.
169
S. Hedges, “Interior Decoration to Exterior Surface: The Beleaguered
Relief”. Interiority, vol. 2, no. 1, 2019, h. 79-93.; E. M. Kavaler, “Ornament and Systems of
Ordering in the Sixteenth-Century Netherlands”. Renaissance Quarterly, vol. 72, no. 4,
2019, h. 1269-1325. 170
A. Iliopoulos, “Early body ornamentation as Ego-culture: Tracing the co-evolution
of aesthetic ideals and cultural identity”. Semiotica, no. 232, 2020, h. 187-233.; S. Supatmo,
“The Manifestation of Cultural Tolerance Value of Traditional Ornament: Study on
Ornaments of Sendang Duwur Mosque-Graveyard, Lamongan, East Java”. In 2nd
International Conference on Arts and Culture (ICONARC 2018), vol. 276, (Atlantis Press,
2019), h. 105-109. 171
R. P. G. Tolentino, “Archaeology of Sacred Symbols: The Lost Meaning and
Interpretations”. International Journal of Recent Innovations in Academic Research, vol. 3,
no. 10, 2019, h. 66-71.; A. Foltarz, “Symbols, Signs, Messages in Ergonomics of Social
Space”. Human-Centered Computing: Cognitive, Social, and Ergonomic Aspects, vol. 3,
2019, h. 200. 172
Batik Yogja dan batik Solo sesuai tempat asalnya, Yogya dan Solo memiliki dimensi
fraktal yang mirip dengan batik dari Madura dan Garut, tetapi batik Madura dan batik Garut
193
Motif batik Cirebon yang sangat kaya dan unik di yakini merupakan hasil
desain dari keluarga keraton, yang sebagian terinspirasi dari motif-motif asing,
termasuk Tiongkok, Arab, dan Eropa. Oleh karena hasil desain dari keluarga
keraton, maka motif batik Cirebon banyak menggambarkan lingkungan istana
seperti Kereta Kencana Paksi Naga Liman, Kereta Kencana Singa Barong, Taman
Guha Air Sunyaragi, keramik Tiongkok, Siti Inggil, Patran Kangkung atau bentuk
Kangkungan,173
termasuk bangunan keraton dan sebagainya. Namun, di antara
motif hias batik Cirebon, yang sangat khas adalah bentuk wadasan dan Mega
Mendung. Lombard mengatakan bahwa batik Cirebon itu desainnya figuratif,
seperti pagar wesi, wadasan, dan Taman Arum. Temanya banyak terinspirasi
langsung oleh dekorasi keraton, termasuk Taman Air Guha Sunyaragi.174
Selain itu,
motif batik Cirebon juga banyak berlatar belakang singgasana sultan yang
digambarkan dengan bentuk binatang (ular naga dan gajah) yang memiliki sayap
burung dan bercahaya seperti “halilintar”.175
Binatang ini digunakan sebagai
kendaraan sultan dan dinamakan Kereta Kencana Paksi Naga Liman atau dalam
istilah Lombard disebut dragon-bird-elephant, termasuk juga Kereta Kencana Singa
Barong yang biasa digunakan Sunan Gunung Jati.176
Beberapa motif inilah yang
menjadi ikon batik Cirebon, sekaligus membedakannya dengan motif batik di
daerah lain.
Batik Cirebon memang banyak mendapat pengaruh dari motif-motif khas
budaya asing. Karena sejak awal Cirebon sebagai kota pelabuhan tentu banyak
dikunjungi oleh para pedagang dari luar seperti Persia, India, Arab dan Tiongkok.
Hubungan dagang yang terjalin dengan para pedagang itu juga memengaruhi
perkembangan ornamen Batik Cirebon. Hal tersebut bisa dilihat dalam beberapa
motif yang sering digunakan yakni motif batik Paksi Naga Liman yang mendapat
pengaruh dari Persia, motif buraq mendapat pengaruh dari Arab, dan motif batik
pangkaan177
soko Tiongkok mendapat pengaruh dari Tiongkok, termasuk pewarnaan
batik yang terang.178
Kalau kita telusuri dalam sejarahnya, batik keraton sebagaimana dijelaskan di
atas awalnya hanya digunakan oleh kalangan keraton dan memiliki makna sakral.
sendiri memiliki dimensi fraktal yang berbeda. Lihat penelitian Y. Hariadi, M. Lukman, &
A. Haldani, “Batik Fractal: From Traditional Art to Modern Complexity”. In Proceeding
Generative Art X Milan Italia, 2007, h. 1-10. 173
Patran Kangkungan memiliki makna persembahan pada Yang Maha Agung. Dalam
arti kata bahwa hidup ini hanya untuk mengabdi kepada Tuhan yang Maha Agung. Biasanya
batik ini dipakai pada upacara ritual. Lihat I. Tambrin, “Batik Cirebon: Tinjauan Ornamen
Batik Trusmi Cirebon”, Jurnal Seni Rupa dan Desain, vol. 2, no. 4. 2002, h. 1-13. 174
D. Lombard, Garden in Java, (Jakarta: EFEO, 2010), h. 71-73. 175
A. Haake, “The Role of Symmetry in Javanese Batik Patterns”. Computers &
Mathematics with Applications, vol. 17, no. 4-6, 1989, h. 815-826. 176
Lombard, Garden in Java, h. 11. 177
Pangkaan (pangka=setangkai daun dan bunga), yang terdiri dari Pangkaan dengan
satu jenis pohon atau bunga, di antaranya Pring Sedapur, Pangkaan Anggrek, Klapa
Setundun, Soko Cino, dan Kembang Suru. Lihat T. Soegiarty, “Ornamen Batik Pesisiran
Daerah Sunda”. Jurnal Dimensi Seni Rupa dan Desain, vol. 13, no. 1, 2016, h. 23-38. 178
Tambrin, “Batik Cirebon…, h.1-13.
194
Namun, pada perkembangannya, termasuk di era sekarang ini, motif-motif tersebut
kemudian digunakan oleh kalangan rakyat biasa, atau umumnya disebut batik
pesisiran. Motif ini baru kembali muncul di pasaran atau perbatikan Cirebon pada
tahun 1970-an. Umumnya masyarakat menggunakan motif keraton untuk
menunjukkan kecintaannya pada sultan dan keluarganya. Batik pesisiran yang
dikembangkan masyarakat nampak pada hiasan batik yang dikembangkannya
karena permintaan pasar, dan sudah menjadi barang dagangan dan sumber ekonomi
masyarakat.
Lombard menjelaskan bahwa pekerjaan membatik dan batik itu sendiri sebagai
hasil karya penduduk lokal. Merujuk pada naskah Sunda tertua bertanggal 1440
Saka/1518 M yang ditemukan di Cirebon Selatan, Lombard179
mengatakan kata
“batik” dalam naskah Sunda disebut dengan kata “tulis” yang lazimnya ketika itu
digunakan untuk menyatakan pembubuhan “malam” ke atas kain. Di samping
penjelasan tentang sembilan motif dalam melakukan “tulis” di atas kain.
Berdasarkan konfirmasi Lombard pada sumber Eropa Daghregister di Batavia yang
tertanggal 8 April 1641, bahwa kata “tulis” dalam naskah Sunda merujuk pada
„batik‟ yang sering digunakan dalam Daghregister ketika memberikan pakaian
Sultan Agung (1622). Misalnya, kalimat “…dilukis biru putih menurut cara
negerinya”. Lombard menyimpulkan bahwa melalui pelabuhan-pelabuhan pesisir,
teknik membatik ini dengan cepat masuk ke daerah Mataram, dan memberikan
kekayaan lokal, yang terus berkembang baik di Cirebon dan Pekalongan di satu sisi
dan di Yogya dan Solo di sisi lain.
Batik keraton umumnya bergaya klasik, memiliki patokan ukuran yang baku,
sangat religius dan memiliki nilai simbolik. Motif batik keraton sangat khas
bentuknya, atau yang popular disebut motif wadasan dan motif Mega Mendung,
sedangkan pada batik pesisiran sangat dominan bentuk geometris dan stilasi
tumbuhan berbentuk pankaan/pangkaan.180
Motif batik yang paling populer dan menjadi ikon batik Cirebon adalah motif
wadasan dan Mega Mendung, bahkan hingga mancanegara. Keduanya merupakan
ornamen batik Cirebon yang banyak mengadopsi ornamen-ornamen yang terdapat
pada benda-benda karya seni dari Tiongkok. Ada yang beranggapan bahwa motif-
motif adaptasi ini awalnya merupakan pesanan dari para saudagar asing yang
kemudian diminati juga oleh pihak keraton. Ssebagai bentuk apresiasi, ornamen-
ornamen resapan tersebut kemudian dipakai sebagai bagian dari batik keraton.
Akulturasi budaya ini diperkuat dengan pernikahan Sunan Gunung Jati dengan
Puteri Ong Tien yang berasal dari Tiongkok. Selain motif Mega Mendung dan
wadasan, batik Cirebon juga berkaitan erat dengan simbol-simbil kosmologi,
misalnya, motif Taman Arum Sunyaragi, Wadas Singa, Patran Kangkung, Wadas
179
D. Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya, Jaringan Asia, jilid 2, (Jakarta: Gramedia-
EFEO, 2005), h. 193-194. 180
Pankaan adalah jenis motif batik yang yang berpola pada lukisan pohon atau
rangkaian bungan, dan sering dilengkapi dengan burung-burung atau kupu-kupu di
dalamnya. Bentuk pankaan termasuk ke dalam kategori motif Batik Semarangan yaitu
motif Piring Selampad dan Kembang Kantil.
195
Mantingan, Ayam Alas, Supit Udang, dan sebagainya. Pada dasarnya motif batik
Cirebon memiliki makna simbolik dan filosofis yang mengandung pesan moral.181
1. Motif Wadasan Mega Mendung
Gambar 15. Motif Wadasan Mega Mendung
Sumber: Dokumentasi Mukhoyyaroh, 2020
Wadasan (karang) adalah salah satu materi terkuat di bumi, tidak lekang karena
cuaca dan tahan terhadap abrasi dan erosi. Tidak heran jika wadasan dijadikan
simbol iman, dan diharapkan iman seseorang itu bisa kuat seperti wadas. Gambar
wadasan yang vertikal yang nampak pada batik bermakna bahwa manusia dalam
beribadah dan beramal sholeh harus selalu bersandar pada keridhoan Allah. Dengan
begitu, iman seseorang harus dijaga dengan banyak ibadah dan beramal sholeh.
Motif wadasan terbentuk dari material karang yang kuat dan kokoh bermakna
kekuatan fondasi keimanan. Adapun bentuk karang yang vertikal menunjukkan
hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Makna ini sudah menjadi ajaran
yang secara turun temurun diajarkan dari mulai masa Pangeran Cakrabuana dan
Syarif Hidayatullah. Sementara motif Mega Mendung bentuknya terlihat seperti
gumpalan-gumpalan awan putih yang mengumpul, yang bermakna kehidupan dunia
atas atau bisa juga dimaknai kebebasan. Motif Mega Mendung sering disandingkan
dengan motif wadasan yang menyimbolkan makna kekuatan dan keteguhan.
2. Motif Sulur Mega Mendung
Gambar 16. Motif Sulur Mega Mendung
Sumber: Dokumentasi Mukhoyyaroh, 2020
181
Nursalim & Sulastianto, “Dekonstruksi Motif Batik…, h. 27-40.
196
Motif Mega Mendung dijadikan alat ungkapan untuk mengungkapkan jenis
tumbuhan Sulur (tumbuhan yang merambat). Makna simbolik dan filosofis dalam
kaitannya dengan Islam, yakni amal yang berkesinambungan, istiqomah dalam
beribadah, dan menjaga tali silaturahmi.
Amal yang berkesinambungan yang dimaksudkan disini adalah istiqamah
dalam ibadah. Istiqamah berasal dari kata qawama yang berarti tegak lurus. Kata ini
biasa dipahami sebagai suatu sikap teguh dalam pendirian, konsekuen, tidak
condong atau menyeleweng ke kiri atau ke kanan dan tetap berada pada garis lurus
yang sudah diyakini kebenarannya.182
Istiqamah juga sering dipahami sebagai sikap
teguh hati atau konsisten. Istiqomah adalah berusaha tetap pada jalan Allah dengan
tetap menjalankan kebenaran dan menunaikan janji, yang berkaitan dengan ucapan,
perbuatan, sikap dan niat. Dengan kata lain, istiqamah adalah upaya menenpuh
jalan yang lurus dengan tidak menyimpang dari ajaran Allah SWT.
Istiqamah adalah konsistensi, ketabahan, kemenangan, keperwiraan dan
kejayaan di antara ketaatan, hawa nafsu dan keinginan. Sikap istiqamah seseorang
akan terlihat ketika menghadapi perubahan dan godaan dalam kehidupannya. Oleh
karena itu, agama memberi penghormatan kepada mereka yang sudah beristiqamah
sebagaimana183
ditegaskan Allah dalam al-Qur‟an surat Al-Fussilat ayat 30.
Istiqamah merupakan sebuah kata yang mudah diucapkan dan diingat, namun
tidak semua orang bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Sikap
istiqamah memerlukan kesungguhan yang senantiasa diiringi dengan kejernihan hati
dan keikhlasan. Kejernihan hati dan keikhlasan akan berpengaruh pada keimanan
dan ketakwaan orang agar stabil dan tidak melemah. Keimanan seseorang yang
sudah stabil akan mendorongnya untuk mengamalkan agama secara utuh. Totalitas
dalam beramal sangat diperlukan karena merupakan bagian dari upaya agar amal
atau ibadah tetap istiqamah. Bagi hamba Allah yang sudah istiqamah dalam
beribadah maka balasannya adalah surga yang sudah disiapkan Allah, yang
kenikmatannya belum pernah kita lihat, kita dengar maupun kita rasakan. Intinya
adalah barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dan keberuntungan selalu
mengiringi hidupnya, maka jalan yang harus ditempuh adalah bersikap istiqamah
dalam beramal. Karena hanya orang-orang yang terpilih yang mampu
mempertahankan sikap istiqamah dalam hidupnya.184
Silaturrahmi berasal dari kata صلة yang artinya hubungan atau
menghubungkan. Adapun kata الرحين atau الرحن jamaknya االرحام berarti rahim atau
peranakan perempuan atau kerabat. Asal katanya dari ar-rahmah (kasih sayang).
Kata ini digunakan untuk menyebut rahim atau kerabat karena dengan adanya
hubungan rahim atau kekerabatan itu, orang-orang berkasih sayang.185
Manusia
sebagai makhluk individu dan makhluk sosial pada dasarnya tidak mampu hidup
182
Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an, (Bandung: Mizan, 1997), h. 284. 183
Muhammad Harfin Zuhdi, “Istiqomah dan Konsep Diri Seorang Muslim”. Religia,
vol. 14, no. 1, 2011, h. 111-128. 184
Mulyono, “Keistimewaan Istiqomah dalam Perspektif Al-Quran”. Imtiyaz, vol. 4, no.
01, 2020, h. 1-15. 185
M. Habibillah, Raih Berkah Harta dengan Sedekah dan Silaturrahmi, cet. I,
(Jogjakarta: Sabil, 2013), h. 123.
197
sendiri di dalam dunia ini, mereka harus berinteraksi antara satu dengan yang lain,
temasuk masyarakat yang ada di Cirebon. Interaksi sosial merupakan hubungan
sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara
kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok
manusia. Interaksi sosial yang merupakan hubungan sosial dalam suatu masyarakat
mendapat perhatian dalam ajaran Islam. Interaksi sosial tersebut dalam Islam
dikenal dengan istilah silaturrahmi.
Pokok atau inti dari kata silaturrahmi adalah rahmat dan kasih sayang.
Menyambung kasih sayang dan menyambung persaudaraan, bisa juga diartikan
sebagai menyambung tali kekerabatan dan menyambung sanak. Hal tersebut sangat
dianjurkan oleh agama untuk keamanan dan ketentraman dalam pergaulan
kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.186
Dalam konteks Islam, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW bahwa
orang yang menyambung bukanlah orang yang membalas kebaikan orang akan
tetapi ia adalah orang yang apabila hubungan kekerabatannya diputuskan maka ia
menyambungnya.187
Ini menandakan bahwa silaturrahmi merupakan interaksi sosial
yang mempunyai banyak manfaat bagi manusia demi untuk mewujudkan
kebahagian di dunia dan di akhirat.
Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya silaturrahmi dan larangan
memutuskannya, sebab, memutuskan hubungan silaturrahmi dapat menimbulkan
masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Rasulullah bersabda: “Tidak ada suatu
dosa yang lebih layak dipercepat hukumannya di dunia oleh Allah kepada
pelakunya di samping (azab) yang disimpan baginya di akhirat daripada zina dan
memutus silaturrahmi”. Hadis ini menjelaskan bahwa sesungguhnya memutuskan
hubungan silaturrahmi termasu dosa. Karena memutuskan silaturrahmi berarti
membuat kerusakan di muka bumi, bahkan Allah SWT mengutuk orang yang
memutuskan hubungan silaturrahmi sebagaimana dalam al-Qur‟an surat
Muhammad [47] ayat 22-23.
Dalam ajaran Islam, hubungan antar sesama khususnya antar sesama anggota
keluarga harus dijaga dengan baik karena keretakan keluarga bisa berakibat sangat
buruk. Ini juga yang diterapkan dalam Kesultanan Cirebon sebagai kesultanan Islam
sangat menjunjung tinggi tali persaudaraan. Hal itu tergambar dari sosok Sunan
Gunung Jati yang bukan hanya sebagai raja tetapi penyebar agama Islam di Pulau
Jawa. Sunan Gunung Jati sebagai seorang raja adalah contoh bagi keluarganya,
bawahannya dan juga masyarakat Cirebon secara umum. Di samping bertindak
sebagai raja, ia juga adalah Waliyullah yang tentu dengan kapasitasnya mengajak
seluruh keluarga dan masyarakat di Kesultanan Cirebon untuk bagaimana menjaga
silaturrahmi di antara sesama, sebab ini adalah bagian dari perintah agama, yakni
agama Islam. Praktek inilah yang kemudian tersirat dalam banyak peninggalan seni
dan budaya Cirebon, salah satunya adalah dalam seni batik. Batik dengan motif
186
R. Syafe‟i, Al-Hadis: Akidah, Akhlak, Sosial dan Hukum, (Bandung: Pustaka Setia,
2000), h. 21. 187
Muhammad bin Isma‟il bin Ibrahim al-Mugirah al-Bukhari, Al-Adab al-Mufrad, juz
I, cet. I, (Beirūt: Dār al-Basyair al-Islamiyah, 1409 H/1989M), h. 37.
198
sulur Mega Mendung dipercaya oleh masyarakat memuat makna simbolik dan
filosofis sebagaimana dijelaskan, untuk tetap dipertahankan dari masa ke masa.
3. Motif Balong Teratai
Gambar 17. Motif Balong Teratai
Sumber: Dokumentasi Mukhoyyaroh, 2020
Kalau kita perhatikan di dalam motif Balong Teratai terdapat gambar di bagian
kanan dan kiri yang simetris. Arti filosofisnya adalah bahwa orang akan
menemukan kebahagiaan jika sudah ada keseimbangan atau keselarasan dalam
hidup baik keselarasan antara manusia dan alam, maupun spiritual dan material.
Masyarakat Jawa pada umumnya, termasuk masyarakat Cirebon memiliki nilai
filosofis yang tinggi. Nilai filosofisnya selalu diukur dengan keseimbangan dan
keselarasan. Filosofi Jawa terkait erat dengan budi-etika-sosial-alam, yakni budi
terkait dengan rasa, etika terkait dengan pergaulan, sosial terkait dengan
masyarakat, dan alam terkait dengan semesta. Semua komponen ini akan
dipertimbangkan untuk mencapai keseimbangan, semata-mata untuk meraih
keluhuran dan ketentraman hidup. Semua itu tercermin dalam ungkapan eling lan
waspada.188
Nilai filosofis masyarakat Jawa yang mencerminkan kehati-hatian dan
keseimbangan dengan alam, antara lain: “Sura dira Jayaningrat, lebur dening
pangastuti” (segala sifat keras hati, angkara murka hanya bisa dileburkan dengan
sikap lemah lembut dan kesabaran). “Memayu hayuning bawana ambrasta dur
hangkara” (hidup di dunia mengutamakan keselamatan, kebahagian, kesejahteraan
serta memberantas sifat angkara murka, serakah, dan tamak). “Urip iku urup”
(hidup harus dapat memberi manfaat bagi orang lain). Aja gumunan, aja getunan,
aja kagetan, aja aleman (tidak mudah heran, tidak mudah menyesal, tidak mudah
terkejut, dan tidak manja). “Ngluruk tanpabala menang tanpa ngasorake sekti
tanpa aji-aji lan sugih tanpa banda” (berjuang tanpa bala, menang tanpa
merendahkan orang lain, berwibawa tanpa kekuasaan, dan kaya tanpa harta).189
Gambar di bagian kanan dan kiri yang simetris pada Balong Teratai juga
bermakna keseimbangan spiritual dan material. Islam mengajarkan keseimbangan
dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terlalu ke kanan, juga tidak terlalu ke kiri,
atau dengan pemaknaan yang lain, dunia dan akhirat harus seimbang. Manusia tidak
188
M. Suryadi, “Nilai Filosofis Peralatan Tradisional Terhadap Karakter Perempuan
Jawa dalam Pandangan Masyarakat Pesisir Utara Jawa Tengah”. NUSA, vol. 13, no. 4, 2018,
h. 567-578. 189
Suryadi, “Nilai Filosofis Peralatan…, h. 567-578.
199
boleh hanya mengejar dunia saja, juga tidak boleh hanya mengejar akhirat.
Rasulullah bersabda “Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup
selamanya dan berbuat untuk akhiratmu seolah-olah akan mati besok”. Hal tersebut
dipertegas lagi oleh Allah dalam al-Qur‟an surat Al-Qashas ayat 77.
Selain dua hal di atas, penulis juga melihat bahwa makna keseimbangan atau
keselarasan juga bisa dikaitkan dengan sifat manusia satu dengan manusia yang
lain. Sebagai contoh pasangan suami istri, terutama yang baru menikah. Biasanya
sifat egoisme dalam hubungan rumah tangga bisa membuat laki-laki dan perempuan
dalam perkawinan tidak bisa bersatu. Oleh karena bertahan pada ego pribadi, maka
masing-masing dari mereka akan menuruti kehendaknya sendiri tanpa
mempertimbangkan sebelah pihak lain. Padahal, pada hakikatnya konsep
perkawinan adalah penyatuan dari dua pribadi yang pada mulanya berbeda. Ketidak
keselarasan ego antara laki-laki dan perempuan dalam pekawinan bisa berujung
pada tidak adanya kerukunan dan keharmonisan rumah tangga. Akibatnya konflik-
konflik rumah tangga akan senantiasa muncul dan menjadikan keluarga tidak
harmonis.
Dalam tradisi etnis Tionghoa, simbol teratai sendiri dimaknai sebagai lambang
kesucian. Sementara konsep keselarasan bisa ditemukan pada beberapa jenis hewan.
Dalam tradisi Tionghoa, misalnya ketika burung phoenix (Hong) dipasangkan
dengan naga, bisa bermakna keserasian atau keseimbangan Yin Yang.190
Sehingga
pada dasarnya, baik dalam tradisi masyarakat Jawa, bangsa Tiongkok maupun
dalam ajaran Islam, konsep keselarasan dan keseimbangan itu bisa ditemukan,
meskipun dengan pendekatan yang berbeda-beda. Tetapi, dalam konteks ini penulis
melihat makna filosofi dari gambar simetris pada motif Balong Teratai adalah
bagian dari kerangka pikir manusia secara kritis untuk memperoleh penyelesaian
sebuah persoalan secara imbang. Semua yang dipikirkan berangkat dari prinsip
kebijakan atau kepatutan. Hasil yang diperoleh tidak ada yang dirugikan serta
memiliki nilai dan manfaat yang cukup tinggi. Kemanfaatan yang diperoleh pun
selalu memiliki keselarasan, baik keselarasan antara manusia dengan alam, manusia
satu dengan manusia yang lain, maupun spiritual dan material.
4. Motif Piring Selampad
Gambar 18. Motif Piring Selampad
Sumber: Dokumentasi Mukhoyyaroh, 2020
190
M. Herwiratno, “Kelenteng: Benteng Terakhir dan Titik Awal Perkembangan
Kebudayaan Tionghoa di Indonesia”. Lingua Cultura, vol. 1, no. 1, 2007, h. 78-86.
200
Motif batik Piring Selampad termasuk dalam motif batik pesisiran dari
Cirebon. Ide awalnya berasal dari susunan piring porselen Tiongkok yang dipakai
sebagai hiasan dinding Astana Gunung Jati dan Keraton Kasepuhan. Batik pesisiran
mendapat banyak masukkan pengaruh budaya dari luar mengingat pada abad ke-16,
Cirebon merupakan pelabuhan yang ramai dikunjungi pedagang dari Timur Tengah
dan Tiongkok. Jika dirunut, Piring Selampad telah hadir sejak ratusan tahun lalu,
namun di zaman sekarang, keberadaan batik ini semakin hilang termakan zaman.
Bagi kolektor dan pencinta batik, Agnes Pinnar dalam acara “Metamorfosa
Piring Selampad” di Galeri Alun-Alun Grand Indonesia, mengatakan Piring
Selampad memiliki filosofi yang sangat mendalam, sebagaimana halnya seniman,
pembatik pun dalam setiap karyanya terdapat passion. Pinnar mengatakan Piring
Selampad adalah perjalanan atau ziarah batin, di mana Piring Selampad adalah
sumber kehidupan yang selalu ingin dibagikan kepada teman. Seperti piring yang
menjadi tempat makan, makanan adalah sumber kehidupan. Piring selampad, lanjut
Pinnar, merupakan alas makan untuk meletakkan makanan terbaik di atasnya.191
Karena itu, ketika kaisar-kaisar Tiongkok memberikan piring porselan sebagai
hadiah kepada Sultan Cirebon, itu bukanlah piring sembarangan.
Batik pada zaman dahulu juga dijadikan sebagai penanda peristiwa. Begitu
pula dengan piring selampad. Pinnar mengatakan, ketika kaisar-kaisar Tiongkok
datang ke Kesultanan Cirebon, para pembatik lokal memberikan tanda atau bentuk
khas dari tamu yang datang. Adanya fenomena pedagang dan Kaisar Tiongkok
datang serta membawa hadiah kemudian mereka melukis Piring Selampad dalam
batik, bukan hanya menjadi sebuah pertanda, sebagaimana yang dikatakan Pinnar di
atas bahwa makna filosofi Piring Selampad bukan sekadar penanda peristiwa, tetapi
juga perjalanan atau ziarah batin bagi pembuatnya karena menurut penulis di
dalamnya ada interaksi antara pembatik dengan Piring Selampad.
Ragam hias pada motif batik Piring Selampad yang kemudian dipindahkan ke
media kain telah berlangsung ratusan tahun yang lalu, namun tidak sepopuler motif
Mega Mendung yang kita kenal saat ini. Seperti namanya, Piring Selampad adalah
motif batik yang terinspirasi dari piring-piring porselen yang terpampang di dinding
Astana Gunung Jati, Cirebon. Pada zaman dahulu, ketika banyak pedagang dan
pejabat Tiongkok datang ke tanah Cirebon, mereka memberi hadiah piring-piring
porselen kepada raja di sana, tentu ini bukanlah hal yang biasa sebab benda-benda
tersebut banyak diabadikan di dalam keraton. Di samping desainnya sangat spesial
dan sejarahnya juga cukup dalam, penulis melihat motif batik ini bukan hanya
sekedar motif batik biasa, namun ada sejarah di baliknya. Selain motif dan warna-
warna batik yang memikat, ada unsur lain yang justru membuat motif Piring
Selampad menjadi berbeda dengan motif batik lainnya. Penulis melihat, karena
ceritanya, orang-orang tertarik sebab ada cerita dibalik motif batik, juga tentu
motifnya indah dan cara pembuatan yang unik dan complicated (rumit), tetapi di
luar semua itu, tetap cerita yang membuat batik itu menjadi spesial.
191
Jujuk Ernawati & Adinda Permatasari, “Sejarah Piring Selampad, Motif Batik
Langka dari Cirebon”. Di ambil dari: https://www.viva.co.id/gaya-hidup/gaya/886954-
sejarah-piring-selampad-motif-batik-langka-dari-cirebon. (Diakses pada 24 Februari, 2017).
201
Motif Piring Selampad yang diambil dari susunan tempelan dinding Astana
Gunung Jati terinspirasi dari kegiatan merayakan yang dilakukan oleh masyarakat.
Selampad yang di ambil dari kata lampadan bermakna menyajikan hidangan untuk
merayakan atau kegiatan selamatan yang dilakukan oleh masyarakat. Sederhananya
Piring Selampad berarti piring yang menyajikan satu menu makanan untuk
selamatan. Motif Piring Selampad memiliki pola ceplok-ceplok, sedangkan
karakteristik motif utamanya disusun secara jarang dan kadang berselang-seling
untuk membuat irama. Sementara isinya (isen; Jawa) yang digunakan adalah bentuk
geometris seperti limaran coret, limaran doktoran dan limaran tembokan.192
Motif Piring Selampad di Kesultanan Cirebon diambil dari keramik yang
ditempel di tembok istana. Maknanya sing eling lampat ing badan yang berarti
manusia harus selalu ingat dan waspada atas perbuatannya. Setiap manusia akan
memetik apa yang sudah diperbuatnya, jadi hati-hati setiap mau melangkah.
Pertimbangkan matang-matang akibat yang akan muncul di kemudian hari. Hal ini
juga dapat ditemui dalam al-Qur‟an surat Ar-Rahman [55] ayat 60. Ayat ini
menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada pahala bagi orang yang berbuat baik
dengan mentaati Tuhannya, kecuali Allah SWT membalasnya dengan pahala yang
baik. Sebaliknya, dalam surat An-Nisaa‟ [4] ayat 123, Allah menegaskan bahwa
barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan
kejahatan itu pula.
Beberapa ayat di atas sesungguhnya ingin menjelaskan balasan terhadap orang-
orang yang beriman dan bertakwa. Allah SWT akan membalas setiap perbuatan
manusia dengan penuh keadilan. Balasan yang didapat seseorang sesuai dengan apa
yang sudah mereka usahakan. Setiap manusia yang melakukan kejahatan akan
mendapat balasan setimpal, dan masuk neraka. Sebaliknya, mereka akan
mendapatkan kehidupan yang baik jika melakukan perbuatan baik pula, dan pada
akhirnya akan masuk surganya Allah. Dan surga digambarkan di nash sebagai
tempat yang indah. Ada taman-taman, sungai-sungai susu, khamar dan madu yang
mengalir, buah-buahan yang beraneka macam dan tidak pernah berhenti berbuah,
minuman yang tidak memabukkan, bidadari-bidadari, pelayan-pelayan yang setia,
pakaian dari sutera, fasilitas lain yang terbuat dari emas, berlian dan permata.193
192
Aditya A. Putri HK & Desi Wulandari, “Analisis Makna Motif Batik Ciwaringin
Cirebon”. Seminar Nasional Seni dan Desain: Reinvensi Budaya Visual Nusantara, Jurusan
Seni Rupa dan Jurusan Desain Universitas Negeri Surabaya, 2019, h. 35-40.; Aditya A.
Putri HK & Zakarias S. Soetejab, “Analysis of the Meaning of Ciwaringin Batik Motifs
Cirebon”. The International Seminar QUOVADIS of Traditional Arts XIII “Diversity in
Culture”, 2017, h. 1-8. 193
Ilyas Daud, “Surga di dalam Hadis”. Farabi: Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang
Filsafat dan Dakwah, vol. 18. no. 2, 2018, h. 1-13.
202
5. Motif Barongsai
Gambar 19. Motif Barongsai
Sumber: Dokumentasi Mukhoyyaroh, 2020
Barongsai merupakan salah satu kesenian tradisional etnis Tionghoa yang
berasal dari Tiongkok. Seni tersebut masih ada dan berkembang sampai sekarang
ini. Kesenian Barongsai bagi masyarakat Tionghoa adalah berfungsi sebagai media
hiburan, ritual dan politik. Barongsai bagi masyarakat Tionghoa memiliki makna
simbolik dan makna strategi. Barongsai adalah lambang keberuntungan, sehingga
bagi masyarakat Tionghoa khususnya yang ada di Cirebon, dan Jawa pada
umumnya percaya jika memberikan angpao kepada Barongsai kelak akan
mendapatkan limpahan rejeki dan keberuntungan dari dewa. Oleh karena itu, pada
saat Imlek atau Cap Go Meh, masyarakat Tionghoa berebut untuk memasukkan
angpao ke mulut Barongsai. Adapun makna strategis Barongsai adalah sebagai
sarana interaksi sosial antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi.
Lewat kesenian ini diharapkan mampu mendekatkan dan merekatkan hubungan
antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat pribumi sehingga jarak di antara
keduanya bisa diminimalisir.194
Pentingnya pemaknaan di atas sebab kehidupan modern saat ini telah
mengarah pada masalah identitas. Keterasingan tidak hanya terjadi dalam dimensi
individu, tetapi juga mereka merasakan keterasingan dalam hubungannya dengan
alam semesta, dan dengan sesamanya (keterasingan sosial). Penulis melihat jika
dalam artikel yang ditulis Putra bahwa kesenian Barongsai bisa menjadi alat untuk
merekatkan dan membina hubungan harmonis antar sesama, maka Yulianto dalam
karyanya “Tasawuf Transformative…” yang digagas oleh Muhammad Zuhri tidak
hanya aktual, tetapi juga relevan untuk “membebaskan” manusia modern dari
berbagai masalah yang mereka hadapi. Memang semangat tasawuf yang dibawa
oleh Zuhri tampak sarat dengan tindakan sosial dan aspek komunal. Tasawuf
transformatf menurut pemikiran Zuhri lebih pada solusi implementatif atas krisis
yang terjadi pada masyarakat modern. Tasawuf transformatif hadir sebagai
penyeimbang atas ketimpangan antara sisi rasionalitas-materialitas dengan sisi
nativisme-spiritual yang memungkinkan seseorang menjadi asketis (zuhud)
194
Bintang Hanggoro Putra, “Fungsi dan Makna Kesenian Barongsai bagi Masyarakat
Etnis Cina Semarang”. Harmonia, vol. IX, no. 1, 2009, h. 1-11.
203
sekaligus berdampak sosial.195
Hal tersebut juga telah disinggung Allah dalam al-
Qur‟an surat Al-Hujuraat [49] ayat 13.
Dari ayat di atas, terlihat bahwa Islam adalah agama berkeadilan dengan
prinsip keadilan Allah yang merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Di hadapan
Allah semua manusia sama, tidak membedakan suku, bangsa, bahasa, warna kulit.
Karena yang membedakan hanya ketakwaannya, sedangkan nilai iman dan
ketakwaan hanya Tuhan yang mengetahui. Keadilan sosial Islam merupakan dasar
penting bagi tegaknya syariat. Keadilan sosial Islam sifatnya mengikat sebagai
sesuatu yang wajib ditaati oleh pemeluknya. Allah memerintahkan dalam banyak
ayat, yang pesan-Nya memotivasi sekaligus mengingatkan supaya tidak
meninggalkan-Nya, terutama dalam hal menetapkan hukum dan menegakkan
keadilan.196
Kemudian, kalau diperhatikan di bawah gambar Barongsai juga ada motif
Mega Mendung yang horisontal, bermakna hablum minan-nas. Manusia dimanapun
berada harus mengembangkan sikap inklusif. Mau bergaul dengan siapa saja dan
dari mana saja, yang penting nilai-nilai Ketuhanan harus selalu dipegang kuat.
Pada dasarnya, riwayat pembentukan bangsa Indonesia, termasuk Cirebon atau
Kesultanan Cirebon ketika itu adalah kisah panjang tentang sebuah komunitas yang
inklusif. Bangsa yang terbuka menerima segala pengaruh apa pun “yang baik” yang
datang dari manapun, tanpa mesti meninggalkan apa yang sudah menjadi miliknya,
ia baik-baik saja menerima dan menyikapi segala pengaruh luar yang menyelinap.
Tidak ada resistensi ketika pengaruh luar itu datang dengan semangat menyebarkan
persaudaraan, tanpa paksaan atau peperangan. Sikap seperti itulah sebenarnya yang
menciptakan tali persatuan pada keberagaman penduduk di wilayah Nusantara ini,
termasuk di Kesultanan Cirebon.
Sejak awal, daerah Cirebon terbuka (inklusif), daerah ini senantiasa menjadi
tuan rumah yang baik, kepada siapa pun well come, dan prasangkanya baik. Dengan
karakteristik yang demikian, bangsa ini secara umum dan Cirebon khususnya, tanpa
disadarinya telah berkembang menjadi sebuah komunitas yang terbentuk lewat
proses hibridisasi yang besar, salah satunya adalah peninggalan budaya Nusantara
atau Indonesia saat ini, yakni batik Cirebon. Maka tidak heran ketika bangsa Eropa
kemudian menyebut wilayah Nusantara sebagai Mooi Indië,197
kepulauan Hindia
yang indah. Tidak hanya itu, inklusivisme penduduk Nusantara juga menjadi
pertimbangan bangsa-bangsa asing untuk datang ke Nusantara, termasuk Cirebon.
D. Guha Sunyaragi
Guha Sunyaragi atau Taman Air Sunyaragi adalah salah satu situs unik yang
terletak di Desa Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Cirebon, dan menempati lahan
195
Rahmad Yulianto, “Tasawuf Transformatif sebagai Solusi Problematika Manusia
Modern dalam Perspektif Pemikiran Tasawuf Muhammad Zuhri”. Teosofi, vol. 4, no. 1,
2014, h. 56-87. 196
Qurratul Ainiyah, “Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pernikahan Islam Sebagai
Bukti Agama Berkeadilan”. Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat, 13 Juli 2018, h.
132-145. 197
D. Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya, (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 43.
204
seluas 15.000 meter persegi.198
Pada awal pembuatannya, Guha Sunyaragi jauh dari
pemukiman masyarakat,199
dan berfungsi sebagai cara atau sekedar mencari
ketenangan pikiran di setiap lorong-lorong gua, sebab suasana di guha itu sepi dan
jauh dari rumah masyarakat. Beberapa literatur menyebut bahwa Guha Sunyaragi
berawal dari danau Segara Amparan Jati yang dikelilingi oleh hutan jati, kemudian
dijadikan sebagai Taman Kelangenan (taman kesenangan), yang fungsi utamanya
adalah untuk ber-khalawatan (menyendiri).200
Ada juga yang menyebut Guha Sunyaragi dengan nama Taman Kaputren
(tempat bermain keluarga sultan), dan tempat penyepi ing ragatempat
bertapa/bersemedi sebagaimana juga dalam kepercayaan agama Hindu.201
Falah
mengatakan bertapa berkaitan dengan kegiatan keagaman, mendekatkan diri pada
Tuhan dan menjauhkan diri dari keramian. Sunyaragi atau kosong jasmani adalah
suatu kondisi yang didapatkan pada saat bertapa atau menyepi.202
Pada intinya,
semuanya mengarah pada maksud yang sama. Adapun yang dimaksud dengan
tempat penyepi ing raga dalam konteks ini adalah tempat keluarga sultan ber-
tawassulialah aktivitas mengambil sarana atau wasilah agar doa atau ibadahnya
dapat diterima oleh Allah. Bagi sultan, tawassul adalah salah satu cara mendekatkan
diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan, beribadah, dan mengikuti
petunjuk rasul-Nya serta mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diridhai-
Nya.203
Kalau kita lihat dalam beberapa literatur, nama Guha Sunyaragi ditulis dengan
nama Goa Sunyaragi, yang menurut penulis meskipun penulisan nama “Goa” dan
“Guha”, perbedaannya hanya dari segi penulisan saja, tetapi menurut Ajat keduanya
memiliki makna yang berbeda.204
Lebih lanjut ia mengatakan “Guha” berarti Goa
buatan manusia dan sengaja dibangun, sedangkan “Goa” bermakna Goa alam, yang
alami dan hasil bentukan alam sendiri, tanpa bantuan manusia.205
Mengacu pada
198
N. Nurudin & F. Nurfalah, Communication Marketing of Youth and Sport
Department of Culture and Tourism in the Water Park Cave Sunyaragi Cirebon City, West
Java, Indonesia. In International Symposium on Social Sciences, Education, and Humanities
(ISSEH 2018), vol. 306, (Atlantis Press, 2019), h. 31-34. 199
Kondisi di masa itu berbeda dengan di masa sekarang, bangunan Guha Sunyaragi
kini telah berubah fungsinya, dan sudah banyak bangunan rumah di sekitar wilayah Guha
Sunyaragi. 200
Nurudin & Nurfalah, “Communication Marketing…, h. 31-34. 201
Shirley Firth, “End-of-life: a Hindu view”. The Lancet, vol. 366, no. 9486, 2005, h.
682-686. 202
W. A. Falah, “Tinjauan Konsepsi Seni Bangunan Istana Peninggalan Masa Islam di
Kesultanan Cirebon dalam Konteks Kesinambungan Budaya”. Dalam Susanto Zuhdi (ed.),
Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra. Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah, (Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996), h. 68. 203
Abdul Aziz, dkk., “Pengelolaan Taman Wisata Goa Sunyaragi”. Al-Musthofa:
Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, vol. 3, no. 1, 2018, h. 134-152. 204
Wawancara dengan Ajat (Budayawan dan Pemandu Taman Air Sunyaragi) pada
tanggal 16 Juli 2020. 205
Wawancara dengan Ajat (Budayawan dan Pemandu Taman Air Sunyaragi) pada
tanggal 16 Juli 2020.
205
catatan sejarah yang ditulis Pangeran Sulendraningrat, Guha Sunyaragi dibangun
pada masa Pangeran Aria Cirebon atau Pangeran Adipati Aria Karangrangen sekitar
tahun 1703. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa tahun itu adalah masa
perbaikan dan penyempurnaan yang pertama kali di kawasan Guha Sunyaragi. Jadi
Guha itu sebenarnya dibangun pada masa PRA Zaenal Arifin (Pangeran Mas) yang
merupakan Sultan Cirebon pertama. PRA Zaenal Arifin adalah putera Syarif
Hidayatullah dari isteri bernama Nyi Mas Tepasari yang asal dari Demak.
Gambar 20. Guha Sunyaragi (Guha Peteng)
Sumber: Dokumentasi Mukhoyyaroh, 2020
Guha Sunyaragi dibangun atas prakarsa Pangeran Kertasari untuk mengganti
Taman Kaputren Nur Giri Sapta Arga (Giri Septa Rengga) yang sudah berubah
fungsi sebagai pasarean atau makam, dimana makam Sunan Gunung Jati dan
keluarganya dimakamkan. Pada saat itu, Raden Sepat dari Demak ditunjuk untuk
mengepalai proyek pembangunan Guha Sunyaragi dengan dibantu oleh para arsitek
dari Tionghoa206
yang sudah lama tinggal di Cirebon. Kebenaran berita ini bisa
dibuktikan dengan adanya monumen Tiongkok. Monumen itu sekilas mirip bong
pai (makam), namun sebenarnya adalah prasasti untuk mengenang bahwa
pembangunan Guha Sunyaragi juga dibantu oleh ahli-ahli seni dari Tiongkok yang
sudah lama tinggal di Cirebon. Maka tidak heran, kalau kemudian bangunan Guha
Sunyaragi banyak dipengaruhi oleh unsur budaya Tionghoa, dan salah satunya
adalah Guha Peteng yang ada di area Guha Sunyaragi mirip dengan bangunan yang
ada di Forbidden City. Hal ini juga dipertegas oleh Duta Besar Tiongkok ketika
mengunjungi situs Guha Sunyaragi.
Guha Sunyaragi secara fisik memang banyak dipengaruhi oleh budaya
Tionghoa dan Hindu. Tetapi menurut analisa penulis, selain dipengaruhi oleh
budaya Tionghoa dan Hindu, juga ada pengaruh Islam, sebab Kesultanan Cirebon
adalah kesultanan Islam. Pengaruh Islam yang penulis maksudkan, tidak melekat
pada bentuk fisik daripada bangunan Guha Sunyaragi, termasuk semua Guha-Guha
kecil yang ada didalamnya, tetapi lebih kepada fungsi dan makna filosofis dari
206
Setelah diteliti ternyata 300 meter dari area Guha Sunyaragi ditemukan banyak
makam etnis Tionghoa dengan huruf Kanji yang tidak bisa dipahami oleh orang Tionghoa
generasi sekarang. Dalam sejarah dikatakan bahwa pengawal Ong Tien ada yang ikut pergi
ke Kuningan, tetapi ada juga yang menetap di Cirebon. Sehingga penulis menyimpulkan
bahwa merekaetnis Tionghoa yang menetap di Cirebon, ketika meninggal, semua
dikuburkan di dekat Guha Sunyaragi.
206
bangunan-bangunan tersebut. Hal tersebut sebagaimana juga yang dijelaskan Ajat
bahwa Guha Sunyaragi secara keseluruhan merupakan gambaran perjalanan hidup
manusia.207
Guha Sunyaragi sebagaimana maknanya adalah tempat penghilangan diri atau
raga guna mencapai kesempurnaan spiritual. Di samping itu, Taman Sunyaragi juga
dijadikan sebagai tempat tinggal (istirahat), juga tempat melatih ilmu kanuragan
dan mental para prajurit.208
Pembangunan Guha Sunyaragi pada dasarnya
mengandung nilai-nilai religious yang ada dalam ajaran Islam, khususnya tasawuf.
Sebagaimana disebutkan di awal bahwa salah satu fungsi Guha Sunyaragi adalah
sebagai tempat berkhalwat para sultan untuk mendapatkan ketenangan batin dan
kesempurnaan spiritual dengan cara berzikir kepada Allah sebagaimana dahulu
Rasulullah SAW melakukan tahannuts di Gua Hiro. Fungsi guha/gua adalah
sebagai tempat berkhalwat sangat bersesuaian dengan salah satu ajaran tasawuf
yang menekankan pendekatan keruhanian melalui khalwat, atau semedi dalam
bahasa Jawa. Penganut tasawuf biasanya melakukan zikir dan bertafakur serta
membersihkan batin dari pikiran tercela dengan cara berkhalwat. Pengertian
tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Allah dalam al-Qur‟an surat Ar Ra‟d
[13] ayat 28, bahwa hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.
Berdasarkan ayat di atas, sebenarnya banyak cara yang dianjurkan agama
untuk dapat membersihkan hatinya. Salah satunya dengan berdzikir dan salawat
kepada Allah. Dzikir adalah salah satu cara yang ditempuh manusia untuk
merelaksasikan pikiran dan hatinya dari berbagai hal. Hati yang bersih akan
menjadi gerbang bagi kebaikan-kebaikan yang lain, bahkan berdasarkan penelitian
Olivia menemukan bahwa zikir bisa menjadi terapi untuk menenangkan jiwa para
lansia yang mengalami hipertesi.209
Oleh karenanya, zikir juga berpengaruh positif
dalam menurunkan kecemasan pasien gagal ginjal kronis (GGK) yang menjalani
hemodialisasi.210
Semua urutan bagunan yang ada di dalam Guha Sunyaragi sebagaimana yang
disebutkan di atas, memiliki fungsi dan makna yang berbeda-beda, yang
berorientasi pada perjalanan hidup manusia, yaitu: pertama, setelah masuk alun-
alun, ada dua buah kolam teratai yang melambangkan bahwa ketika manusia akan
terlahir ke dunia, didahului darah dan air ketuban.
207
Wawancara dengan Ajat (Budayawan dan Pemandu Taman Air Sunyaragi) pada
tanggal 16 Juli 2020. 208
Franseno Pujianto, Desain Lansekap Taman Sari: Objek Studi Goa Sunyaragi
Cirebon, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas katolik
Parahyangan, 2012), h. 19.; Lihat juga Firda Rasyidian, dkk., “Spatial Principles and
Ornamentsation on Water Garden Relics of Kesultanan Cirebon: Case Student Witana Water
Garden, Pakungwati Water Garden, and Sunyaragi Water Garden”. Jurnal Risa, vol. 03, no.
04, 2019, h. 363-380. 209
Olivia Dwi Kumala, dkk., “Efektifitas Pelatihan Dzikir dalam Meningkatkan
Ketenangan Jiwa pada Lansia Penderita Hipertensi”. Psympathic: Jurnal Ilmiah Psikologi,
vol. 4, no. 1, Juni 2017, h. 55-66. 210
Iin Patimah, dkk., “Pengaruh Relaksasi Dzikir Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien
Gagal Ginjal Kronis yang Menjalani Hemodialisa”. Jurnal Keperawatan Padjajaran, vol. 3,
no. 1, 2015, h. 18-24.
207
Kedua, Guha Pengawal. Guha adalah tempat istirahat pengawal sultan dan
keluarganya ketika berkunjung ke Guha Sunyaragi. Orang tua biasanya rewel ketika
anak perempuannya hamil. Anaknya disuruh bawa gunting, lidi dan lain-lain
kemanapun pergi untuk jaga-jaga.
Ketiga, Bangsal Jinem. Bangunan berbentuk podium di sepanjang tribun ini
adalah tempat dimana sultan dan keluarganya duduk sambil menyaksikan para
prajurit yang sedang berlatih ilmu kanuragan, juga pada saat menyaksikan
pertunjukan tarian tradisional dalam acara-acara yang dilangsungkan oleh
Kesultanan Cirebon seperti tarian pegas topeng khas Cirebon.211
Kata jinem sendiri
terdiri dari dua kata yaitu ji sama artinya dengan siji (satu), sedangkan nem sama
artinya dengan nenem (enam). Dalam Islam ada rukun iman yang jumlahnya enam,
dan iman sesorang harus selalu dijaga agar tetap kuat. Puncak dari iman adalah
iman kepada Allah yang Esa. Dengan demikian, jika iman setiap orang Muslim
terjaga, maka hidupnya akan senantiasa di jalan Allah.
Keempat, Mande Beling. Secara harfiah Mande Beling dapat diartikan sebagai
tempat yang bening. Karena dahulu tempat ini terbuat dari marmer, bening seperti
kaca. Mande Beling dahulunya difungsikan sebagai tempat sultan memberikan
wejangan, petuah atau nasehat kepada masyarakat atau tamu yang berkunjung ke
Guha Sunyaragi. Makna filosofis dari Mande Beling adalah manusia yang sering
mendengar nasehat agama, hatinya akan tenang dan pikirannya jernih.
Kelima, Kolam Kaputren. Kolam ini adalah merupakan tempat bermain air
para putera dan puteri sultan ketika berada di area Guha Sunyaragi. Dahulu
sekeliling kolam dihiasi ornamen piring dari Tiongkok. Tatapi berdasarkan
pengamatan penulis di lapangan, tempelan ornamen-ornamen Tiongkok tersebut
sudah hilang, sehingga yang tertinggal hanya bekas tempelannya saja. Itulah
sebabnya Nurudin dan Nurfalah menilai kondisi Guha Sunyaragi saat ini sangat
memprihatinkan, karena ada beberapa fasilitas yang tidak terpelihara dengan
baik,212
termasuk tempelan ornamen piring dari Tiongkok, yang sebenarnya benda-
benda tersebut harus dijaga karena merupakan bagian dari peninggalan budaya
masala lalu. Kolam Kaputren bermakna bahwa setiap anak yang baru lahir harus
dialiri air, dimandikan dan dibersihkan. Di samping itu, setiap anak yang lahir
dalam tradisi Kesultanan Cirebon harus diperdengarkan adzan di telinga kanan dan
iqomat di telinga kiri, supaya “padang atinya” yang dilambangkan dengan Guha
Padang Ati.
Kolam Kaputren letaknya persis di belakang Guha Peteng yang mirip dengan
bangunan di Forbidden City, maknanya manusia lahir dalam kegelapan, makanya
harus diadzani dan diiqomati supaya padang atinya. Di atas Guha Peteng ada
cungkup Guha Punyit maknanya manusia ketika kecil senyum-senyum sendiri,
tertawa sendiri sambil diawasi sedulur papat. Kata orang tua manusia bangga ono
sedulur papat, kelima pancer yang ngawasi. Manusia itu lahir ke alam dunia tidak
sendiri. Karena sedulur papat itu di antaranya adalah roh dan darah. Artinya,
sempurnakan dirimu sebagaimana kamu lahir untuk kamu kembali. Setelah dewasa
berada dalam kebimbangan untuk menentukan pilihan yang dilambangkan dengan
211
Nurudin & Nurfalah, “Communication Marketing…, h. 31-34. 212
Nurudin & Nurfalah, “Communication Marketing…, h. 31-34.
208
Bale Kambang. Setelah lolos dari kebimbangan, akan menjadi Arga Jumudyaitu
orang yang diambil petuahnya, ilmunya dan dituruti sarannya. Ketika hidup carilah
amal ibadah yang dilambangkan Pelataran Pande Kemasan. Para ahli kemasan itu
bikin cinderamata. Buat apa kemasan (amal ibadah)? Buat bekal kita menuju alam
kelanggengan yang dilambangkan dengan Guha Kelanggengan. Guha
Kelanggengan pintu keluarnya dibelakang kereta gajah . maknanya adalah setelah
dapat bekal banyak, kita tinggal menuju alam kelanggengan ditarik pakai Buraq
menuju Sidratul Muntaha. Itu tujuan amal ibadah umat Islam.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, Guha Sunyaragi termasuk bangunan
guha-guha kecil di dalamnya nampak sempit dan rendah. Arsitektur bangunan yang
seperti itu memiliki makna filosofis tersendiri dalam Kesultanan Cirebon. Ajat
mengatakan, gaya arsitektur dari bangunan Guha Sunyaragi yang sempit dan rendah
semuanya mengandung makna filosofis, yakni manusia sehebat apapun harus
mengamalkan “ilmu padi” (semakin berisi semakin merunduk). Desain arsitektur
dari guha-guha yang rata-rata pendek membuat manusia yang mampu memasukinya
harus merunduk. Ini menandakan juga bahwa menjadi manusia tidak boleh
sombong, sebab dalam sejarah, perilaku sombong adalah yang pertama kali
dilakukan oleh iblis. Iblis merasa dirinya mulia sehingga ketika Allah perintahkan
bersujud kepada Adam, iblis enggan melakukannya. Karena sifat sombongnya,
maka iblis terusir dari surga dengan cara yang amat hina. Allah melarang dan
membenci hamba-hambanya yang sombong karena sifat ini sangat tidak baik dan
akan mendatangkan kemudharatan kepada pelakunya. Kesombongan dapat merusak
hubungan persaudaraan, pertemanan dan dapat menumbuhkan benih-benih
kebencian. Sifat sombong bisa membuat seseorang hilang rasa sayang dan empati
kepada orang lain. Hal tersebut ditegaskan Allah dalam al-Qur‟an surat Luqman
[31] ayat 18.
Ketidaksukaan Allah terhadap sikap sombong ini telah diabadikan dalam
berbagai ayat, termasuk kisah-kisah kesombongan orang-orang terdahulu seperti
Firaun yang menolak seruan Musa untuk beriman kepada Allah, dan kisah Kan‟an
(putera nabi Nuh) yang tidak mau mengikuti ajakan ayahnya untuk menaiki
perahunya. Peristiwa tersebut diabadikan dalam al-Qur‟an surat Hud ayat 40-48.213
Kaitannya dengan konteks penelitian ini adalah bahwa lewat makna bangunan
guha-guha kecil yang ada di Guha Sunyaragi memuat pesan positif, yakni agar
manusia menjauhi sifat sombong, dan agar manusia tidak dihinggapi sifat ini, maka
selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan banyak zikir, sebab
zikir yang dilakukan secara istiqomah akan mampu membersihkan diri dari segala
penyakit hati, termasuk sifat sombong. Adapun dengan ruangan yang sempit
bermakna bahwa kelak di akhirat, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan
amalnya sendiri-sendiri. Kalau manusia bisa lolos dari kesempitan itu, maka di
dalamnya akan terasa legah dan lapang.214
Dengan demikian, pada dasarnya semua
bangunan di dalam Guha Sunyaragi menggambarkan perjalanan hidup manusia.
213
Hasiah, “Mengintip Prilaku Sombong dalam Al-Quran”. Jurnal El-Qanuny, vol. 4,
no. 2, 2018, h. 185-200. 214
Wawancara dengan Ajat (Budayawan dan Pemandu Taman Air Sunyaragi) pada
tanggal 16 Juli 2020.
209
Gambar 21. Guha Sunyaragi (Bahan Dasar: Batu Karang)
Sumber: Dokumentasi Mukhoyyaroh, 2020
Makna lain yang ada didalam bangunan Guha Sunyaragi terletak pada bahan
dasar pembuatan guha itu sendiri, yakni batu karang, yang meskipun sejenis batu
tetapi pada dasarnya masih bisa dengan mudah dihancurkan atau mudah retak. Batu
karang melambangkan bahwa memang kehidupan itu keras, namun di alam aslinya
karang itu seperti rumput, mudah lentur. Sederhananya, keras tidaknya kehidupan
yang dialami dan dijalani oleh manusia, tergantung seberapa besar usaha dan
seberapa mampukah manusia menaklukan kerasnya hidup, termasuk masalah utama
manusia yakni melawan hawa nafsu, sebagaimana Ajat mengatakan bahwa yang
dimaksud masalah disini adalah masalah utama yang dihadapi manusia yakni
melawan hawa nafsu, sebab tidak mudah bagi manusia untuk mampu menundukkan
hawa nafsu.215
Seorang Muslim yang memiliki tingkat keimanan yang baik kepada Allah,
niscaya akan istiqomah untuk tidak meninggalkan prinsip yang dipegang sekalipun
harus berhadapan dengan berbagai resiko maupun tantangan besar dalam hidup.
Lebih jauh, seorang Muslim yang sudah istiqomah dengan keimanannya akan dapat
mengontrol dirinya dan mengendalikan hawa nafsunya dengan baik. Namun yang
perlu diperhatikan adalah bahwa perkara menundukkan hawa nafsu butuh
perjuangan yang sungguh-sungguh, sebab musuh terbesar manusia adalah hawa
nafsunya. Orang sudah konsisten dengan keimanannya akan selalu berpikiran
positif, dan membuatnya dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh kedamaian
dan kemudahan.216
Terkait dengan perkara menjaga keimanan, Rasulullah bersabda:
“Dari Hisyam bin „Urwah dari bapaknya, dari Sufyan bin Abdullah al-
Tsaqafi r.a berkata: “aku berkata: “Wahai Rasulullah! Katakanlah satu
perkataan padaku tentang Islam yang aku tidak perlu menanyakannya kepada
orang lain. “Sabda Rasulullah SAW: “Ucapkanlah aku beriman dengan Allah
kemudian beristiqomahlah kamu” (HR. Muslim).
Rasulullah SAW melalui hadis di atas, mengajak umat Islam agar selalu
menjaga keimanannya dan menyuruh beristiqamah untuk tetap berpegang pada
aturan-aturan Allah sehingga pada akhirnya mendapat predikat muttaqin. Kaitannya
dengan penelitian ini, sekalipun dari segi arsitektur pengaruh Hindu dan Tionghoa
215
Wawancara dengan Ajat (Budayawan dan Pemandu Taman Air Sunyaragi) pada
tanggal 16 Juli 2020. 216
Muhammad Harfin Zuhdi, “Istiqomah dan Konsep Diri Seorang Muslim”. Religia,
vol. 14, no. 1, 2011, h. 111-128.
210
begitu kental mewarnai Guha Sunyaragi, namun sarat dengan nilai-nilai Islam.
Selain arsitektur dasarnya adalah batu karang, bangunan Guha Sunyaragi juga
dikelilingi air. Maka dari itu, untuk sampai ke Guha Sunyaragi, setiap orang harus
menggunakan getek atau rakit. Pada dasarnya air merupakan sumber kehidupan
makhluk hidup, sehingga itu harus dihormati dan hargai. Air juga berfungsi sebagai
pengaman dan kenyaman sultan dan keluarga serta pendingin dan penyejuk ruangan
Guha Sunyaragi. Di samping, air juga memudahkan orang berwudhu bagi yang
akan melakukan semedi dan ibadah-ibadah lainnya di kompleks Guha Sunyaragi.
Dengan demikian, tidak heran jika semua ruangan guha dialiri air.
Dalam budaya Tiongkok, angin dan air dipercaya merupakan komponen
penting untuk membentuk perilaku dan sifat alam (semua makhluk) di bumi dalam
mengisi peradaban manusia. Penataan dan penempatan energi angin dan air yang
tepat dapat melimpahkan keberuntungan bagi kehidupan. Air juga melambangkan
spiritualitas, kedamaian, mistis, kontemplasi, kesabaran, kepercayaan, stabilitas dan
melankolis.217
Masyarakat Tionghoa sangat mempercayai Feng Shui. Feng Shui
merupakan worldview yang dipercaya masyarakat Tionghoa sebagai bagian dari
budaya terapan yang terkait dengan kehidupan keseharian. Feng Shui merupakan
media transformasi konsep pemikiran falsafah alam semesta yang rumit dan
beragam lalu digabungkan secara harmonis agar dapat diterapkan pada bentuk yang
terukur dan terjangkau oleh panca indera manusia dalam bentuk bangunan.218
Feng
Shui terdiri dari dua suku kata, yaitu Feng/Hong yang berarti angin dan Shui yang
berarti air. Dalam Feng Shui dipercaya bahwa manusia, surga (astronomi), dan
bumi (geografi) hidup dalam harmoni untuk membantu memperbaiki hidup dengan
menerima Qi (energi) positif.219
Guha Sunyaragi adalah bangunan paling unik di ASEAN yang diciptakan oleh
manusia seperti berbentuk laut dan gunung bebatuan. Konstruksi dan komposisi
situs bangunan adalah taman air. Dari sisa-sisa yang ada, terlihat kecanggihan dan
hasil keunikan budaya manusia pada zamannya. Guha Sunyaragi adalah
peninggalan budaya kuno, yang merupakan bagian dari Keraton Kasepuhan.
Meskipun fungsi berubah sesuai dengan kehendak para penguasa pada zamannya,
tetapi garis besar Guha Sunyaragi adalah tempat dimana para pangeran atau prajurit
istana dipenjara karena kekuatan ilmu kanuragan. Guha Sunyaragi sebagai guha
terbesar di Keraton Kasepuhan sekurangnya telah mengalami beberapa kali
direstorasi, baik pada masa Sultan Sepuh IX, di era kolonial dan sekarang. Tercatat
pada saat ini dipulihkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selama
delapan periode (sejak tahun anggaran 1977/1978 hingga tahun anggaran 1984/1985
yang lalu, ditambah dengan perbaikan pagar-pagarnya pada tahun 1989/1990 dan
1990/1991).220
Kemudian, revitalisasi Guha Sunyaragi selanjutnya pada tahun 2014
adalah paket dengan revitalisasi Keraton Kasepuhan.
217
Monica, “Feng Shui dalam Mendesain Logo”. Humaniora, vol. 2, no. 1, 2011, h.
132-138. Lihat juga Sugiri Kustedja, dkk, “Feng-Shui: Elemen Budaya Tionghoa
Tradisional”. Melintas, vol 28, no. 1. 2012, h. 61-89. 218
Kustedja, “Feng-Shui: Elemen Budaya Tionghoa Tradisional”, h. 61-89. 219
Monica, “Feng Shui dalam Mendesain Logo”, h. 132-138. 220
Nurudin & Nurfalah, “Communication Marketing…, h. 31-34.
213
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kontak sosial-budaya etnis Tionghoa dengan masyarakat Cirebon terjadi
melalui tiga gelombang, yaitu dimulai sejak abad ke-15, yang ditandai dengan
kedatangan Cheng Ho dan para pasukannya; Gelombang kedua terjadi pada
akhir abad ke-15, yang ditandai dengan kedatangan Puteri Tiongkok bernama
Ong Tien Nio dengan seluruh barang bawaannya; Gelombang ketiga terjadi di
abad ke-18, ditandai dengan masuknya orang-orang Tionghoa sebagai orang-
orang pelarian dari Batavia.
Kontak sosial-budaya etnis Tionghoa dan Cirebon dalam perkembangannya
turut membuat kedua kebudayaan terakulturasi, dan menemui puncaknya pada
akhir abad ke-15 melalui pernikahan Sunan Gunung Jati dengan seorang puteri
Tionghoa bernama Ong Tien Nio. Seandainya Sultan tidak beristerikan orang
Tionghoa boleh jadi budaya-budaya Tionghoa itu tidak akan mewarnai Keraton
Kasepuhan dan budaya fisik lainnya di Kesultanan Cirebon. Ini menjadi bukti
bahwa Lembaga perkawinan mampu menghasilkan pembauran yang berkulitas
dan alamiah berupa akulturasi. Ornament Tionghoa yang begitu kuat tidak dapat
dilepaskan dari peran etnis Tionghoa yang hadir, utamanya puteri Ong Tien Nio,
yang tidak hanya fisik tapi juga jiwanya. Ong Tien adalah sosok yang sangat
berarti bagi Sunan Gunung jati. Ini juga menjadi bukti betapa berperannya
seorang perempuan dalam ruang dan makna, sehingga turut mewarnai ruangan-
ruangan kesultanan yang begitu private seperti keraton Kasepuhan, Astana
Gunung Jati, Kereta Kencana Singa Barong, batik Mega Mendung, Guha
Sunyaragi, dan sebagainya.
Berbagai bukti arkeologis memperlihatkan bahwa di dalam keraton
Kasepuhan dan beberapa wujud budaya fisik lainnya terdapat berbagai budaya
yang ikut mewarnai. Makna filosofisnya adalah bahwa sekalipun Cirebon
merupakan Kesultanan Islam, tapi sangat terbuka terhadap dinamika masyarakat
dan bersikap inklusif terhadap berbagai budaya dan keberagamaan orang lain.
Kesultanan ini ingin berdiri diatas keberagaman budaya dan meletakkan
penghormatan yang tinggi terhadap keyakinan orang lain. Kesultanan Cirebon
sangat menghormati dan menghargai leluhurnya, dengan tetap mengakomodir
unsur-unsur Hindu, yang secara filosofis bermakna penghormatan terhadap yang
lebih tua sebab Hindu sudah lebih dulu ada dibanding Islam. Orang Hindu yang
melihat Gapura Candi Bentar merasakan keterwakilannya, begitupun dengan
etnis Tionghoa melihat ornamen-ornamen Tionghoa yang begitu kental. Dari
berbagai simbol yang ada memperlihatkan bahwa Kesultanan Cirebon sarat
dengan nilai-nilai ketauhidan dan menginginkan adanya kerukunan hidup
beragama dan berbudaya dalam kehidupan bernegara.
214
B. Saran dan Rekomendasi
Secara historis dan geografis, Cirebon merupakan salah satu daerah di Jawa
Barat yang sejak awal menjadi tempat perjumpaan berbagai kalangan mengingat
daerah ini selain menjadi tempat berdirinya kesultanan Islam, juga menjadi pusat
perdagangan di masa lalu karena dilengkapi fasilitas berupa pelabuhan
internasional. Sebagai kota yang sejak awal menjadi tempat perjumpaan orang-
orang dari berbagai manca negara, tentu tidak dapat dipungkiri terjadi sebuah
akulturasi budaya, baik budaya material maupun non material, yang hingga saat
ini masih bisa kita temukan di Kesultanan Cirebon. Sementara penelitian ini
penulis fokuskan atau lebih banyak membahas mengenai budaya material berupa
benda-benda peninggalan, baik budaya Cirebon maupun budaya material yang
mendapat pengaruh dari Tionghoa dimulai sejak etnis ini memasuki daerah
Cirebon. Sehingga itu, tema penelitian ini penulis fokuskan pada akulturasi
budaya Tionghoa dan budaya Cirebon di Kesultanan Cirebon. Tentu masih
banyak yang perlu dikaji mengenai kebudayaan yang ada di Cirebon, yang hal-
hal tersebut luput dari kajian ini. Bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya,
penulis menyarankan sekaligus merekomendasikan beberapa hal yang dapat
dijadikan sebagai fokus kajian selanjutnya dalam kaitannya dengan kebudayaan
di Kesultanan Cirebon. Pertama, budaya Cirebon yang mendapat pengaruh dari
luar, selain budaya yang mendapat pengaruh Tionghoa. Kedua, budaya non
material Tionghoa yang terakulturasi dengan budaya Cirebon. Ketiga, perlu
ditelusuri lebih jauh soal benda-benda peninggalan lain, yang luput dari
penelitian ini. Untuk mengkaji hal-hal tersebut, tentu membutuhkan tenaga dan
waktu yang tidak sedikit, utamannya menyangkut pelacakan arsip-arsip yang
sampai sekarang sebagian besar belum ditemukan.
Selain bagi para akademisi dan peneliti, penulis juga merekomendasikan
beberapa hal kepada pemerintah setempat. Pertama, Pemerintah Provinsi Jawa
Barat dan Kota Cirebon diharapkan dapat memberikan perhatian ekstra terhadap
benda-benda bersejarah yang ada di Cirebon, sehingga tetap terpelihara dengan
baik. Kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Cirebon serta dinas
terkait dapat bersinergi membuat kebijakan-kebijakan: (1) memasukkan materi
kebudayaan Cirebon dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal (Mulok) di sekolah-
sekolah jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah
Menengah Atas; (2) Mengagendakan kegiatan studi sejarah rutin di tempat-
tempat bersejarah peninggalan Kesultanan Cirebon. Sehingga, para siswa dapat
mengenal sejarah kota Cirebon, termasuk seluruh benda peninggalannya. Ketiga,
Pemerintah Daerah Cirebon dan dinas terkait di kota Cirebon, budayawan, dan
penggiat budaya, serta masyarakat Cirebon hendaknya ikut berperan aktif dalam
pementasan-pementasan budaya, baik di tingkat lokal, nasional maupun
internasional.
215
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abdurrahman, P. R. Cerbon, (Jakarta: Yayasan Mitra Budaya Indonesia dan
Penerbit Sinar Harapan, 1982).
Adeng, dkk. Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra, (Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998).
Afif, A. Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri,
(Depok: Penerbit Kepik, 2012).
Agus, Bustanuddin. Al-Islam, Buku Pedoman Kuliah Mahasiswa untuk Mata
Ajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).
Agustian, A. G. Rahasia Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ;
Emotional Spiritual Quotient Berdasarkan 1 Ihsan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun
Islam, (Jakarta: Arga Wijaya, 2001).
al-Haddad, Habib Abdullah bin Alwi. Nasehat-nasehat Agama dan Wasiat-wasiat
Keimanan, terj. Zaid H. Al-Hamid, cet. I, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2002).
Alim, Muhammad. Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan
Kepribadiam Muslim, (Bandung: Rosda Karya, 2006).
al-Jāwy, Muḥammad Nawawī. Riyāḍ al-Badī‟ah, (Semarang: Pustaka al-‗Alawiyah,
t.th.).
Ambary, H. M. ―Peranan Cirebon sebagai pusat perkembangan dan penyebaran
Islam‖, dalam S. Zuhdi, Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra (Jakarta:
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI, 1996).
Ambary, H. M. Peranan Cirebon sebagai pusat perkembangan dan penyebaran
Islam, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997).
Ang, I. ―Trapped in Ambivalence Chinese Indonesians, victimhood and the Debris
of History‖. In Morris, M. & de Bary, B. (eds.), „Race‟ Panic and the Memory
of Migration, (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2001).
Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. Mutiara Hadis, cet. V, Jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang,
19780).
al-Asqalani, Fatḥul-Bari Syarh Sahih Bukhari, jilid 1. (Kairo: Dar al-Hadis, t.th.)
al-Asqalani, Hafizh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar. Fatḥul-Bari Syarh Sahih
Bukhari, jilid 1. (Kairo: Dar al-Hadis, t.th.).
al-Attas, S. M. N. Islam, Secularism and The Philosophy of the Future, (Kuala
Lumpur: ISTAC, 1985).
al-Attas, S. M. N. The Intuition of Existence, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1990).
Atja, Carita Purwaka Caruban Nagari: Karya Sastra sebagai Sumber Pengetahuan
Sejarah, (Bandung: Proyek Pemuseuman Jawa Barat, 1986).
Atja, Nagarakretabumi, (Bandung: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan
Sunda (Sundanologi), Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1986).
Atja, Tjarita Purwaka Tjaruban Nagari, (Jakarta: Ikatan Karyawan Museum, 1972).
Aubrey, N. ―A Dwelling Place for Dragons: Wild Places in Mythology and
Folklore‖. In The Psychology of Religion and Place, (Cham: Palgrave
Macmillan, 2019).
216
Ayatrohaedi. Dialektologi sebuah pengantar (An introduction to dialectology),
(Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979).
Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad
XVII-XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia,
(Bandung: Mizan, 1994).
Azra, Azyumardi. Jaringan UlamaTimur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad
XVII dan XVIII, cet. IV, (Bandung: Mizan, 1998).
Badwailan, Ahmad bin Salim. Dahsyatnya Terapi Shalat, terj. Ubaidillah S.
Akhyar, (Jakarta: Nakhlah Pustaka, 2007).
Barzilai, G. Communities and Law: Politics and Cultures of Legal Identities,
(University of Michigan Press, 2003).
Basyarahil, Abdul Aziz Salim. Shalat; Hikmah, Falsafah dan Urgensinya, (Jakarta:
Gema Insani Press, 1996).
Beirne, P. ―On Gabriel Tarde, Penal Philosophy‖. In Classic Writings in Law and
Society: Contemporary Comments and Criticisms, (London & New York:
Routledge, 2017).
Berger, P. L. dan Luckmann, T. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang
Sosiologi Pengetahuan, (Jakarta: LP3ES, 1990).
Blusse, Leonard. Strange Company: Chinese Settlers, Mestizo Women, and the
Dutch in VOC Batavia, (Amsterdam: Foris Publication, 1988).
Bochari, M. S. & Kuswiyah, Wiwi. Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon,
(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001).
Borshalina, T. ―Development of Entrepreneurship and Sustainable Innovation in
Indonesian Small and Medium Enterprises (Study on Trusmi Batik SMEs in
Cirebon, West Java, Indonesia)‖. The 11th Asian Academy of Management
International Conference 2015, (Universiti Sains Malaysia, APEX, Asian
Academy of Management, Majelis Profesor Negara, Yayasan Pahang, 2015).
Boulger, Demetrius C. The Life of Sir Stamford Raffles, (London: Horace Marshal
& Son, 1897).
Budiman, A. Masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia (The Chinese Muslim
Community in Indonesia), (Semarang: Tanjung Sari, 1979).
Budiman, Amen. Masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia, (Semarang, Tanjung
Sari, 1979).
al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. Sahih al-Bukhari, juz I,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1981).
al-Bukhari, Imam. Ṣahīḥ Bukhōrī Kitāb Tafsīr al-Qur‘ān Bab Surat Luqman Ayat
34, vol. 6, (Beirūt: Dār Ibn Tuq al-Najāḥ, 1422 H.).
al-Bukhari, Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim al-Mugirah. Al-Adab al-Mufrad,
juz I, cet. I, (Beirūt: Dār al-Basyair al-Islamiyah, 1409 H/1989 M).
Cator, W. J. The Economic Position of the Chinese in the Netherlands Indies,
(Oxford: 1936).
Chittick, N. Kilwa: An Islamic Trading City on the East African Coast, vol. II,
(Nairobi/London: British Institute of African Studies, 1974).
Clyne, M. & Jupp, J. (ed.), ―Epilogue: A Multicultural Future‖. In Multiculturalism
and Integration: A Harmonious Relationship, (ANU Press, 2011).
217
Connorton, Paul. How Does Society Remember, Nazi Biligo (translation),
(Shanghai: People's Publishing House, 2000).
Coogan, M. D. Eastern Religions: Hinduism, Buddhism, Taoism, Confucianism,
Shinto, (Duncan Baird Publishers, 2005).
Cortesao, A. The Summa Oriental of Tome Pires, (London: Hakluyt Society 1994).
Creswell, J. W. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed,
(Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
Darmayanti, T. E. & Bahauddin, A. ―The Influence of Foreign and Local Cultures
on Traditional Mosques in Indonesia‖. In Islamic Perspectives Relating to
Business, Arts, Culture and Communication, (Singapore: Springer, 2015).
Dartano, Penyebaran Agama Islam di Cirebon dan Sekitarnya antara Tahun 1470-
1570 M, (Universitas Indonesia, 1991).
Dasuki, H. A. (ed.), Sejarah Indramayu, (Indramayu: Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Indramayu,1978).
Dasuki, H. A. Purwaka Caruban Nagari, (Indramayu: Pustaka Nasional, 1978).
de Graaf, H. J. & Pigeaud, Th. G. Th. Chinese Muslim in Java in The 15 th And 16
th Centuries: The Malay Annals of Semarang and Cerbon. Edited by M. C.
Ricklefs, (Melbourne: Monash University, 1984).
de Graaf, H. J. dkk. Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI: Antara Historisitas
dan Mitos, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998).
de Haan, F. Oud Batavia, (Bandung: 1935).
de Saussure, F. ―Course in General Linguistics‖, In Literary Theory, An Anthology,
by J. Rivkin & M. Ryan (eds.), (UK: Blackwell Publishing Ltd., 2004).
Djaja, Tamar. Pusaka Indonesia: Riwayat Hidup Orang-orang Besar di Tanah Air,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1965).
Djajadiningrat, H. Beberapa Catatan Mengenai Kerajaan Jawa Cerbon pada Abad-
abad Pertama Berdirinya, (Jakarta: Bhratara, 1973).
Donley-Reid, L. W. ―The power of Swahili Porcelain, Beads and Pottery‖. In S. M.
Nelson, A.B. Kehoe (eds.), Powers of Observation: Alternative Views in
Archaeology, Archaeological Papers of the American Anthropological
Association 2, (Washington: American Anthropological Association, 1990).
Dupoizat, M. F., Wibisono, N. H, & Guillot, C. Catalogue of the Chinese-Style
Ceramics of Majapahit: Tentative Inventory, (Paris & France: Association
Archipel, 2007).
Dwipayana, G. dan Hadimadja, R. K. Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan
Saya, (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1989).
Dyah, S. A. & Zein, F. K. ―The Influence of Cultural Acculturation on Architecture
Keraton Kasepuhan Cirebon‖. In Reframing the Vernacular: Politics,
Semiotics, and Representation, (Cham: Springer, 2020).
Ekajati, E. S. (ed.), Masyarakat Sunda dan Kebudayaannya, (Jakarta: Girimukti
Pasaka, 1984).
Ekajati, E. S. dkk, Sejarah Cirebon Abad Ketujuh Belas, (Bandung: Kerjasama
Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat dan Universitas Padjajaran,
1991).
Ekajati, E. S. Sejarah Kuningan: Dari Masa Prasejarah sampai Terbentuknya
Kabupaten, (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2003).
218
Erwantoro, H. Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon, (Bandung: Balai Pelestarian
Sejarah dan Nilai Tradisional, 2012).
Falah, W. A. ―Tinjauan Konsepsi Seni Bangunan Istana Peninggalan Masa Islam di
Kesultanan Cirebon dalam Konteks Kesinambungan Budaya‖. Dalam Susanto
Zuhdi (ed.), Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra. Kumpulan Makalah Diskusi
Ilmiah, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996).
Fleisher, J. & Laviolette, A. ―The Changing Power of Swahili Houses, Fourteenth
to Nineteenth Centuries AD‖. In R. A. Beck (ed.), The durable house: House
Society Models in Archaeology, Center for Archaeological Investigations
Occasional Paper, no. 35, (Carbondale, Southern Illinois University, 2007).
Gan, C. ―Archaeological Finds and Origins of Chinese Civilization‖. In A Concise
Reader of Chinese Culture, (Singapore: Springer, 2019).
Geertz, C. The Interpretation Cultures, (New York: Basic Books Inc. Publisher,
1973).
Gex, De Jeny. Asian Style Source Book, (Singapura: MQ Publication Ltd., 2000).
Giap, T. S. ―Islam and Chinese assimilation in Indonesia and Malaysia‖. In Chinese
Beliefs and Practices in Southeast Asia, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications,
1993).
Gilhuly, K., Ackerman, R., Adams, J. N., Ahl, F., Alvares, J., Anderson, B.,
Anderson, W. S. et al. ―Cultic Prostitution: A Case Study in Cultural
Diffusion‖. In Erotic Geographies in Ancient Greek Literature and Culture,
vol. 51, no. 1/2, (New York: Center for Hellenic Studies, 2018).
Gillin & Gillin, Cultural Sociology: A Revision and of an Introduction to Sociology,
(New York: The Macmillan Company, 1954).
Groeneveldt, W. P. Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from
Chinese Sources, (Jakarta: Bhratara, 1960).
Habibillah, M. Raih Berkah Harta dengan Sedekah dan Silaturrahmi, cet. I
(Jogjakarta: Sabil, 2013).
Hall, Stuart. ―Cultural Identity and Diaspora‖, dalam Jonathan Rutherford, (eds.),
Identity: Community, Culture, Difference, (London: Lawrence and Wishartm,
1990).
Harb, T. Rihlah Ibn Battutah al-Musammah Tuhfah al-Nuzzar fi Ghara‟ib al-Amsar
wa Aja‟ib al-Asfar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002).
Hardesty, D. L. ―The Use of General Ecological Principles in Archaeology‖. In
Advances in Archaeological Method and Theory, vol. 3, (New York:
Academic Press, 1980).
Hardjasaputra, A. S. Cirebon dalam Lima Zaman: Abad Ke-15 hingga Pertengahan
Abad Ke-20, (Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Budaya Provinsi
Jawa Barat, 2012).
Hardjasaputra, A. S. dan Haris, T. (ed.). Cirebon dalam Lima Zaman: Abad ke-15
hingga Pertengahan Abad ke-20, (Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat, 2011).
Harsojo, Pengantar Antropologi, (Bandung: Binacipta, 1967).
Haviland, W. A. Antropologi, terj. Soekadijo, R. G. (Jakarta: Erlangga, 1988).
Haviland, W. A. Cultural Anthropology, (Wadsworth Publishing Company, 2002).
219
Hawwa, Said. Al-Islam, terj. Badul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press,
2004).
Herkovits, M. J. Acculturation: The Study of Culture Contact, (New York: Peter
Smith, 1958).
Hernawan, W. & Kusdiana, Ading. Biografi Sunan Gunung Djati: Sang Penata
Agama di Tanah Sunda, (LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).
Hidayat, Raden S. Sejarah Caruban Kawedar, (Cirebon: Badan Komunikasi
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, 2008).
Hidayat, Z. M. Masyarakat dan Kebudayaan Cina di Indonesia, (Bandung: Tarsito,
1984).
Hoebel, E. A. Man in the Primitive World: An introduction to Anthropology, vol. 1,
(New York: Toronto: McGraw-Hill Book Company, 1949).
Horton, P. B. & Hunt, C. L. Sociology (New York: McGraw-Hill, 1976).
Huan, Ma. Ying-yai Sheng-Ian: The Overall Survey of the Ocean's Shores
(1433).Translated by J. V. G. Mills. Edited by Feng Ch‘eng Chun, (Cambridge:
The University Press for the Hakluyt Society, 1970).
Huang, J. Budaya Etnis Tionghoa Cirebon, (Cirebon, 2006).
Huang, Jeremy. Mengungkap Keberadaan dan Budaya Etnis Tionghoa Cirebon,
(Cirebon: Katalog Online Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati, 2006).
Ibn Rajab, Ahmad al-Hambali. Jami‟ul-„Ulum wal Hikam, (Beirut: Darul Ma‘rifah,
1987).
al-‗Id, Ibn Daqiq. Syarah al-Arba‟in Hadisan al-Nawawiyah, (Kairo: Maktabah
Turos al-Islami, t.th.).
Idi, A. & Huda, N. Cina-Melayu di Bangka, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009).
Irianto, H. R. B. dan Sutarahardja, K. T. Sejarah Cirebon: Naskah Keraton
Kacirebonan, (Yogyakarta: Deepublish, 2013).
Ismawati, ―Budaya dan Kepercayaan Jawa Masa Pra-Islam‖, dalam Darori Amin
(ed.), Islam dan Kebudayaan Jawa, (Yogyakarta: Gama Media, 2000).
Jary, David dan Jary, Julia. HarperCollins Dictionary of Sociology, (New York:
HarperPerennial, 1991).
Joe, Liem Tian. Riwayat Semarang 1416-1931, (Semarang: 1933).
Johan, I. M. Penelitian Sejarah Kebudayaan Cirebon dan Sekitamya Antara Abad
XV-XIX: Tinjauan Bibliografi, dalam Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra,
(Jakarta: Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia,
1996).
Joseph, A. D. Komunikasi Antar Manusia, (Jakarta: Professional Books, 1997).
Joyomartono, M. Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat dalam Pembangunan,
(Semarang: IKIP Semarang Press, 1991).
K. Yuanzi, Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah Cheng Ho,
(Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2007).
Kampah, Ki. Babad Cirebon Carub Kandha Naskah Tangkil, (Cirebon: Rumah
Budaya Nusantara Pesambangan Jati Cirebon, 2013).
Ke, X. ―Person-making and Citizen-Making in Confucianism and their Implications
on Contemporary Moral Education in China‖. Re-envisioning Chinese
Education: The Meaning of Person-making in a New Age, (London: Routledge,
2015).
220
Keesing, F. M. Culture Change: An Analysis and Bibliography of Anthropological
Sources to 1952, (New York: Stanford University Press, 1953).
Keesing, F. M. Culture Change: An Analysis and Bibliography of Anthropological
Sources to 1952, no. 1. (New York: Octagon Books, 1973).
Keesing, R. M. & Keesing, F. M. New Perspectives in Cultural Anthropology, (New
York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1971).
Kemenkumham, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang
Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat
China Tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic of Indonesia and the
People‟s Republic of China on Extradition), (Jakarta: Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia, 2016).
Kementrian Agama RI., Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Solo: Fatwa, 2016 M/ 1437
H).
Kern, R. A. & Djajadiningrat, H. Masa Awal Kerajaan Cirebon, (Jakarta: Bhratara,
1974).
Kersten, C. ―The Caliphate‖. In Oxford Research Encyclopedia of Religion, 2019.
Kertawibawa, B. B., Pangeran Cakrabuana Sang Perintis Kerajaan Cirebon, vol. 1
(Bandung: PT. Kiblat Buku Utama, 2007).
Kite, E. ―Chinese Cultural Identity: Suharto's Wisdom and its Success in Achieving
Complete Integration‖. In ACICIS Field Report, (Malang: Muhammadiyah
University, 2004).
Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, (Jakarta: Dian Rakyat,
1977).
Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta: Djembatan,
1990).
Koentjaraningrat, Metode-Metode Antropologi dalam Penyelidikan-Penyelidikan
Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia,
1958).
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Yogyakarta: 1981).
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990).
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015).
Kong, Yuanzhi. Muslim Tionghoa Cheng Ho, (Jakarta: Pustaka Populer Obor,
2000).
Kong, Yuanzhi. Sam Po Kong dan Indonesia, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1996).
Kristeva, J. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art, (New
York: Columbia University Press, 1980).
Kyngäs, H. ―Qualitative Research and Content Analysis‖ In The Application of
Content Analysis in Nursing Science Research, (Cham: Springer, 2020).
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‘an Badan Litbang & Diklat Kementrian Agama
RI dengan LIPI, Air dalam Perspektif Al-Qur‟an dan Sains, (Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur‘an, 2011).
Laksmiwati, D. K. Putri Ong Tien Mengarungi Samudra Asmara Meraih Cinta
Sejati Susuhunan Jati Romantika Caruban Nagarai, cet 2, (Yogyakarta:
Deepublish, 2014).
Lan, Nio Joe. Peradaban Tionghoa Selayang Pandang, (Jakarta: Kepustakaan
Populer Gramedia, 2013).
221
Lapian, A. B. & Sedyawati, E. ―Kajian Cirebon dalam Kajian Jalur Sutra‖. Cirebon
sebagai Bandar Jalur Sutra (Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah), (Jakarta:
Departemen Pendidikandan Kebudayaan RI, 1997).
Lauer, R. H. Perspektif tentang Perubahan Sosial, terj., (Jakarta: Rineka Cipta,
1993).
Leimgruber, W. ―Values, Migration, and Environment: An Essay on Driving Forces
Behind Human Decisions and their Consequences‖. In Environmental Change
and its Implications for Population Migration, (Dordrecht: Springer, 2004).
Liliweri, A. ―Prasangka Sosial dan Efektivitas Komunikasi Antar Etnik di Kupang‖.
Dalam A. Liliweri (ed.), Perspektif pembangunan: Dinamika dan tantangan
pembangunan Nusa Tenggara Timur, (Kupang: Penerbit Yayasan Citra Insan
Pembaru, 1994).
Liliweri, A. Meaning of Culture and Intercultural Communication, (Yokyakarta:
LKIS, 2003).
Liu, H. & Zhou, Y. ―New Chinese Capitalism and the ASEAN Economic
Community‖. In The sociology of Chinese capitalism in Southeast Asia,
(Palgrave Macmillan, Singapore, 2019).
Lombard, D. & Salmon, C. ―Islam and Chineseness‖. In A. Gordon (ed.), The
Propagation of Islam in the Indonesian-Malay Archipelago, (Kuala Lumpur:
Malaysian Sociological Research Institute, 2001).
Lombard, D. Garden in Java, (Jakarta: EFEO, 2010).
Lombard, D. Nusa Jawa: Silang Budaya, Jaringan Asia, jilid 2, (Jakarta: Gramedia-
EFEO, 2005).
Lombard, Dennys Nusa Jawa Silang Budaya: Jaringan Asia, (Jakarta: 1996).
Lowie, R. H. The History of Ethnological Theory, (New York: Holt, Rinehart &
Winston, 1937).
Lubis, N. H. Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat, (Bandung: Alqaprint, 2000).
Lukito, Ratno, Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia,
(Jakarta: Logos, 2001).
Mahfud, Choirul. Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016).
Malik, Ridwan. Puasa Ulat: Merenungi Jejak Tuhan, Bercermin pada Nurani,
(Cibubur: PT. Variapop Group, 2006).
Mariam, S. B. Qualitative Research and Case Study Application in Education, (San
Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 1998).
Masduqi, Z. Cirebon dari Kota Tradisional Ke Kota Kolonial, (Cirebon: Nurjati
Press, 2011).
Masduqi, Z., dkk. Islamisasi, Suksesi Kepemimpinan, dan Awal Munculnya
Kerajaan Islam Cirebon: Kajian dan Penulisan Sejarah Kesultanan Cirebon,
(Jakarta: Puslitbang Lektur & Khazanah Keagamaan Balitbang Diklat
Kementrian Agama RI, 2012).
Menzies, G. 1421: The Year China Discovered America, (New York: Perennial.
2003).
Mikami, Ts. Tôji no michi – tôzai bunmei no setten o tazunete [Jalan Keramik:
Bukti Materiel dari Kontak Budaya Timur dan Barat], (Tokyo: Iwnami Shoten,
1969).
Moleong, L. J. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 1995).
222
Muhaimin, A. G. Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon, (Jakarta:
PT. Logos Wacana Ilmu, 2002).
Muljana, S. Runtuhnya kerajaan Hindu-Jawa dan timbulnya negara-negara Islam
di Nusantara, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005).
Mulyana, Slamet. Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara
Islam di Nusantara, (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2007).
Munro, T., Form and Style in the Arts: An Introduction to Aesthetic Morphology,
Cleveland: Press of Case Western Reserve University, 1970).
an-Nawawi, Imam. Hadits Arbain al-Nawawiyah, edisi terjemahan, (Surabaya: AW
Publisher, 2005).
an-Nawawi, Imam. Syarah Hadits Arba‟in Imam Nawawi Penjelasan 40 Hadits Inti
Ajaran Islam, terj. Ibn Daqiq al-‗Id, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013).
Nio, J. L. Tiongkok Sepandjang Abad, (Djakarta: Gunung Agung, 1952).
Noer, N. M. Menusa Cirebon, (Cirebon: Dinas Pemuda dan Pariwisata Kota
Cirebon, 2009).
Nugrahanto, Widyo. Bertahan di Perantauan: Wacana Cina Muslim di Nusantara
Abad ke 15 dan ke 16, (Bandung: Uvula Press, 2007).
Oetama, J. dan Maarif, A. S. Penyerbukan Silang Antar Budaya: Membangun
Manusia Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 2015).
Ondawame, J. O. ―West Papua: The Discourse of Cultural Genocide and Conflict
Resolution‖. In Cultural Genocide and Asian State Peripheries, (New York:
Palgrave Macmillan).
Onghokham, Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Cina: Sejarah Etnis Cina Indonesia,
(Jakarta: Komunitas Bambu, 2008).
Parlindungan, M. O. Pongkinangolngolan Sinambela gelar Tuanku Rao: Terror
Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak 1816-1833, (Djakarta:
Tandjung Pengharapan, 1964).
Parlindungan, M. O. Pongkinangolngolan Sinambela gelar Tuanku Rao: Terror
Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak 1816-1833, (Yogyakarta:
LKiS, 2007).
Perry, W. J. The Children of the Sun, (London: Methuen, 1923).
Perry, W. J. Gods and Men. The Attainment of Immortality, (London: G. Howe ltd.,
1927).
Pirazzoli-T‘Serstevens, M. ―La route de la céramique‖, Le grand Atlas de
l‟archéologie, (Paris: Encyclopaedia Universalis, 1985).
Pires, Tome. Suma Oriental, edited & translated by Armando Cortesso, (London:
1944).
Pires, Tome. Summa Oriental, terj. Sri Margana, (Yogyakarta: Penerbit Ombak,
2014).
Powell, J. W. Seeing Things Whole: The Essential John Wesley Powell, (Island
Press, 2004).
Pradines, S. Fortifications et Urbanisation en Afrique Orientale, (Oxford:
Archaeopress, 2004).
Pujianto, Franseno. Desain Lansekap Taman Sari: Objek Studi Goa Sunyaragi
Cirebon, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas katolik Parahyangan, 2012).
223
Purcel, V. The Chinese in Southeast Asia, (Kuala Lumpur: Oxford University Press,
1962).
Purwanto, Hari. Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
Puspito, Hendro. Sosiologi Semantik, (Yogyakarta: Kanisius, 1989).
Pusponegoro, M. D. dan Notosusanto, N. Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1991).
Qardhawi, Yusuf. Thaqafatuna Bayna Al-Infitah Wa Al-Inghilaq, (Cairo: Dar al-
Shuruq, 2000).
Qordhawi, Yusuf. Karakteristik Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
Quthub, Sayyid. Tafsir fi Zilali Qur‟an: Di Bawah Naungan Al-Qur‟an, (Jakarta:
Gema Insani, 2001).
al Qurtuby, S. Arus Cina-Islam-Jawa: Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa
dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV&XVI, (Yogyakarta:
Inspeal Ahimsya Karya Press, 2003).
Raffles, S. Memoir of the Life and Public Services of Sir Thomas Stamford Raffles,
(New York: Cambridge University Press, 2013).
Rahardjo, Supratikno (ed). Kota Dagang Cirebon sebagai Bandar Jalur
Sutera, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998).
al-Raḥmān, Abd. Durūs al-Fiqhiyyah, (T.tp.: Maktabah Syekh Salim, t.th.).
Ricklefs, M. C. The History of Modern Indonesia Since c. 1200, vol. 3, (Great
Britain: Palgrave Macmillan, 2001).
Rosyidin, D. N. dkk, Kerajaan Cirebon, (Jakarta: Puslitbang Lektor Khazanah
Keagamaan Balitbang Kementrian Agama RI, 2013).
Rosyidin, D. N. dan Syafaah, A. Keragaman Budaya Cirebon: Survey atas Empat
Entitas Budaya Cirebon, (Cirebon: Elsi Pro, 2016).
Rosyidin, D. N. Ulama Paska Sunan Gunung Jati, Studi atas Sejarah dan Jaringan
Intelektual Cirebon Pada Abad ke 16 Hingga Abad ke 18, (Laporan penelitian,
IAIN Syekh Nurjati, 2014).
Rukmana, A. dan Lembong, E. (ed.). Penyerbukan Sialng Antarbudaya:
Membangun Manusia Indonesia, (Jakarta: Penerbit PT. Elex Media
Kompatindo, Jakarta, 2015).
Rusmin Tumanggor dkk, Ilmu Sosial & Budaya Dasar, (Jakarta: Kencana, 2010)
Saebani, B. A. Pengantar Antropolog, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
Schmader, T., Bergsieker, H. B. & Hall, W. M. ―Cracking the Culture Code‖. In
Applications of Social Psychology by J. Forgas, K. Fiedler & W. Crano (ed.),
(New York: Routledge, 2020).
Schottenhammer, A. ―China‘s Increasing Integration into the Indian Ocean World
Until Song 宋 Times: Sea Routes, Connections, Trades‖. In Early Global
Interconnectivity Across the Indian Ocean World, vol. I, (Cham: Palgrave
Macmillan, 2019).
Sen, T. T. Cheng Ho and Islam in Southeast Asia, (Singapore: Institute of Southeast
Asian Studies, 2009).
Sergi, G. L'uomo secondo le origini, l'antichità, le variazioni e la distribuzione
geografica. Sistema naturale di classificazione. Con 212 figure nel testo, 107
224
tavole separate e una carta geografica dei generi umani, (Fratelli Bocca,
1911).
Setijadi, C. Ethnic Chinese in contemporary Indonesia: Changing Identity Politics
and the Paradox of Sinification, (Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute,
2016).
Setiono, B. G. Tionghoa dalam Pusaran Politik, (Jakarta: Trans Media, 2008).
Shihab, M. Quraish, Membumikan Al-Qur‟an, (Bandung: Mizan, 1997).
Shihab, M. Quraish. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan, cet. XXX,
(Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006).
Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah, vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mișbah, vol. 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, Juz
I-XXX, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
Shiraishi, T. An Age in Motion. Popular Radicalism in Java 1912-1926, (Ithaca:
Cornell University Press, 1990).
Simuh, Sufisme Jawa, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999).
Sirry, M. A., Sejarah Fiqih Islam; Sebuah Pengantar, (Surabaya: Risalah Gusti,
1996).
Skinner, W. G. ―Creolized Chinese Societies in Southeast Asia‖. In A. Reid (ed.),
Sojourners and Settlers: Histories of Southeast Asia and the Chinese,
(Sydney: Allen and Unwin, 1996).
Smith, G. E. In the Beginning: Origin of Civilisation, (New York: Morrow, 1928).
Smith, G. E. The Influence of Ancient Egyptian Civilization in the East and in
America, (America: The University Press, 1916).
Soekanto, S. Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas, (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
Soemardjan, S. dan Soemardi, S. Setangkai Bunga Sosiologi, (Jakarta: Yayasan
Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964).
Soemardjan, S. Perubahan Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1991).
Soemardjan, S. Streotip, Asimilasi, Integrasi Sosial, (Bandung: Cita Karya, 1976).
Sudjana, T. D. Pelabuhan Cirebon Dahulu dan Sekarang, (Jakarta: Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1995).
Sulendraningrat, P. S. (ed.). Sejarah Cirebon dan Silsilah Sunan Gunung Jati
Maulana Syarif Hidayatullah, (Cirebon: Sekretariat Sementara Keprabonan,
1984).
Sulendraningrat, P. S. Babad Tanah Sunda/Babad Cirebon, (1984).
Sulendraningrat, P. S. Sejarah Cirebon, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985).
Sulistiyono, S. T. ―Dari Lemahwungkuk hingga Cheribon: Pasang Surut
Perkembangan Kota Cirebon sampai Awal Abad XX‖, dalam S. Zuhdi,
Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
kebudayaan RI, 1996).
Sulistiyono, S. T. Dari Lemahwungkuk hingga Cheribon: Pasang Surut
Perkembangan Kota Cirebon sampai Awal Abad XX, (Jakarta: Departemen
Pendidikan dan kebudayaan RI, 1997).
Sunano, Muslim Tionghoa di Yogyakarta, (Yogyakarta: Penerbit Mata Bangsa,
2017).
225
Sunardjo, U. Masa Kejayaan Kerajaan Cirebon: Kajian dari Aspek Politik dan
Pemerintahan, (Cirebon: Yayasan Keraton Kasepuhan, t.th.).
Sunardjo, U. Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan
Cerbon, 1479-1809, (Bandung: Tarsito, 1983).
Suryadinata, L. Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia, (Jakarta: Kompas,
2010).
Suryadinata, L. Negara dan Etnis Tionghoa; Kasus Indonesia, (Indonesia: Pustaka
LP3S, 2002).
Suryadinata, L. Pemikiran Politik Etnis Tionghoa 1900-2002, (Jakarta: PT. Grafiti
Press, 2005).
Sutirto, T. W. Perwujudan Kesukubangsaan Kelompok Etnik Pendatang, (Pustaka
Cakra, 2000).
Sutoyo, Anwar. Manusia dalam Perspektif Al-Qur‟an, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2015).
Suyono, A. Kamus Antropologi, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985).
Syafe‘i, R. Al-Hadis: Akidah, Akhlak, Sosial dan Hukum, (Bandung: Pustaka Setia,
2000).
Syamsurizal, dkk., Ikhtisar Sejarah Singkat Syekh Quratul‟ain, (Karawang:
Mahdita, 2009).
Tang, Y. ―On the Dao De Jing (Tao Te Ching)‖. In Confucianism, Buddhism,
Daoism, Christianity and Chinese Culture, (Berlin, Heidelberg: Springer,
2015).
Tanggok, M. I. Menghidupkan Kembali Jalur Sutra Baru: Format Baru Hubungan
Islam Indonesia dan Cina, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010).
Tatt, Ong Hean. Chinese Animal Symbolisms, (Selangor Darul Ehsan: Pelanduk
Publications, 1993).
Tatt, Ong Hean. Simbolisme Hewan Cina, (Jakarta: Kesaint Blanc, 1996).
Taylor, E. B. Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology,
Philosophy, Religion, Art, and Custom, vol. 2, (London: John Murray,
Albemarle Street, 1871).
Thomas, W. I. & Znaniecki, F. The Polish peasant in Europe and America:
Monograph of an immigrant group, vol. 2, (University of Chicago Press,
1918).
Tian, Z., Ye, S. & Qian, H. ―The Flying Dragon and the Dancing Phoenix: Chinese
Totem Myths‖. In Myths of the Creation of Chinese, (Singapore: Springer,
2020).
Tim Peneliti, Sejarah Cirebon Abad Ketujuh Belas, (Bandung: Pemda TK. I, 1991).
Tim Penulis, Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra, (Jakarta:
Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, 1998).
Tjandasasmita, Uka. Bandar Cirebon dalam Jaringan Pasar Dunia, (Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995).
Tjandrasasmita, Uka Arkeologi Islam Nusantara, (Jakarta: Kepustakaan Populer
Gramedia. 2009).
Tjandrasasmita, Uka Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota Muslim di
Indoneisa, (Kudus: Menara Kudus, 2000).
226
Triandis, H. C. & Bhawuk, D. P. S. ―Culture Theory and the Meaning of
Relatedness‖. In P. C. Earley & M. Erez (eds.), The New Lexington Press
Management and Organization Sciences Series and New Lexington Press
Social and Behavioral Sciences Series. New Perspectives on International
Industrial/Organizational Psychology, (The New Lexington Press/Jossey-Bass
Publishers, 1997).
Turner, B. S. The Cambridge Dictionary of Sociology, (UK: Cambridge University
Press, 2006).
Tylor, E. B. Primitive Culture, (New York: Harper Torch Books, 1871).
Tylor, J. G. ―The Chinese and the Early Centuries of Conversion to Islam in
Indonesia‖. In Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting, T.
Lindsey & H. Pausacker (ed.), (Singapore & Australia: ISEAS Publication &
Monash University Press, 2005).
Usman, A. B. dkk. Upacara Sekaten dalam Pendekatan Teologis: Merumuskan
Kembali Interkasi Islam-Jawa, (Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2004).
Usman, A. R. Etnis Cina Perantauan di Aceh, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2009).
van den Berg, L. W. C. Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara, (Jakarta: INIS,
1989).
van der Chijs, J. A. Nederlansch-Indisch Plakaatboek 1602-1811. Vijftiende Deel
(1808-1809). (Batavia/'s Hage: Landsdrukkerij/M. Nijhoff, 1896).
Wahid, A. ―Beri Jalan Orang Cina‖, dalam J. Jahja (peny.), Nonpri di Mata
Pribumi, (Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1991).
Wahid, A. Mengurai Hubungan Agama dan Negara, (Jakarta: Grasindo, 1999).
Wahyu, A. N. Sajarah Wali Syeikh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati: Naskah
Kuningan, alih aksara dan bahasa A. N. Wahju, (Bandung: Penerbit Pustaka,
2007).
Wahyu, A. N. Sajarah Wali Syeikh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati: Naskah
Mertasinga, alih aksara dan bahasa A. N. Wahju, (Bandung: Penerbit Pustaka,
2005).
Weng, H. W. Berislam Ala Tionghoa: Pergulatan Etnisitas dan Religiusitas di
Indonesia, (Jakarta: Mizan, 2019).
Wickley, John. Myths and Literature, Pan Guoqing, et al. (translation), (Shanghai:
Shanghai Literature and Art Publishing House, 1995).
Wiryomartono, B. ―Patrimonial Figure and Historic Sites in Banda Aceh and
Demak‖. In Traditions and Transformations of Habitation in Indonesia,
(Singapore: Springer, 2020).
Wiryomartono, B. ―Urbanism and Ethnic Minority: Chinese Quarters and Society in
Jakarta-Indonesia 1600 – Present‖. In Traditions and Transformations of
Habitation in Indonesia, (Singapore: Springer, 2020).
Xiaoxiang, L. Origins Chinese People and Customs, (Jakarta: Elex Media
Komputindo, 2003).
Ya'qub, Hamzah. Filsafat Agama: Titik Temu Akal dengan Wahyu, (Jakarta:
Pedoman Ilmu Jaya, 1992).
Yuanzhi, Kong. Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah di
Nusantara, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2007).
227
Yuanzhi, Kong. Silang Budaya Tiongkok Indonesia, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu
Populer, 2005).
Zuhdi, S. Hubungan Pelabuhan Cirebon dengan Daerah Pedalaman: Suatu Kajian
dalam Kerangka Perbandingan dengan Pelabuhan Cilacap 1880-1940,
(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997).
Jurnal, Prosiding, dan Makalah
Abadi, M. A. M. ―Cross Marriage (Sebuah Model Pembauran Budaya Antar
Komunitas Cina, Arab, India, Jawa dan Madura di Sumenep Kota)‖. KARSA:
Journal of Social and Islamic Culture, vol. 12, no. 2, 2012, h. 132-148.
Abbink, J. ―Religion and Violence in the Horn of Africa: Trajectories of Mimetic
Rivalry and Escalation between ‗Political Islam‘and the State‖. Politics,
Religion & Ideology, 2020, h. 1-22.
Abidin, Y. Z. ―Keberagamaan dan Dakwah Tionghoa Muslim‖. Ilmu Dakwah:
Academic Journal for Homiletic Studies, vol. 11, no. 2, 2017, h. 357-368.
Abramitzky, R., Boustan, L. & Eriksson, K. ―Do Immigrants Assimilate More
Slowly today than in the past?. American Economic Review: Insights, vol. 2,
no. 1, 2020, h. 125-41.
Afghoni, A. ―Makna Filosofis Tradisi Syawalan (Penelitian Pada Tradisi Syawalan
di Makam Gunung Jati Cirebon)‖. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, vol.
13, no. 1, 2017, h. 48-64.
Agustina, I. H., Djunaedi, A., Sudaryono, S. & Suryo, D. ―Gerak Ruang Kawasan
Keraton Kasepuhan‖. Jurnal Perencanaan Wilayah dan nKota, vol. 13, no. 1,
2013, h. 8-13.
Agustina, I. H., Djunaedi, A., Sudaryono, S. & Suryo, D., ―The Perspective of
Sustainable in Relation Space at Region of Kasultanan Kasepuhan Cirebon‖,
Makalah dipresentasikan dalam International Conference ICABE di IIUM,
Kuala Lumpur, 7th–8th November, 2013.
Agustina, I. H., Hindersah, H. & Asiyawati, Y. ―Identifikasi Simbol-Simbol
Heritage Keraton Kasepuhan‖. ETHOS: Jurnal Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat, vol. 5, no. 2, 2017, h. 167-174.
Ainiyah, Qurratul. ―Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pernikahan Islam Sebagai
Bukti Agama Berkeadilan‖. Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat, 13
Juli 2018, h. 132-145.
al-Aoufi, H., Al-Zyoud, N. & Shahminan, N. ―Islam and the cultural
conceptualisation of disability‖. International Journal of Adolescence and
Youth, vol. 17, no. 4, 2012, h. 205-219.
Alajmi, A. ―‗Ulama and Caliphs New Understanding of the ―God's Caliph‖
term‖. Journal of Islamic Law and Culture, vol. 13, no. 1, 2011, h. 102-112.
Alatas, S. F. ―Notes on various theories regarding the Islamization of the Malay
archipelago‖. Alatas, SF (1985). Notes on Various Theories Regarding the
Islamization of the Malay Archipelago. The Muslim World, vol. 75, 1985, h.
162-175.
228
Alfirdaus, L. K., Hiariej, E. & Adeney-Risakotta, F. ―The Position of Minang-
Chinese Relationship in the History of Inter-ethnic Groups Relations in
Padang, West Sumatra‖. Jurnal Humaniora, vol. 28, no. 1, 2016, h. 79-96.
Ali, M. ―Chinese Muslims in Colonial and Postcolonial Indonesia‖. Explorations,
vol. 7, no. 2, 2007, h. 1-22.
Alkatiri, Z., Waworuntu, A. L., Gani, F. & De Archellie, R. ―Medan Chinese and
Their Stigma: Grabbing Power in Multicultural Society. International Review
of Humanities Studies, vol. 4, no. 1, 2019.
Andawari, M. S., Prabowo, S. & Angge, I. C. ―Makna Simbolik Ornamen Gandhik
dan Wadidang Keris Saidi‖. Jurnal Pendidikan Seni Rupa, vol. 3, no. 1, 2015,
h. 113-118.
Anna, D. N. ―Konghucu di Korea Kontemporer dan Sumbangannya Terhadap
Kerukunan Umat Beragama di Indonesia‖. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, vol.
12, no. 2, 2016, h. 239-254.
Anshori, D. S. ―The Construction of Sundanese Culture in the News Discourse
Published by Local Mass Media of West Java‖. Lingua Cultura, vol. 12, no. 1,
2018, h. 31-38.
Antony, R. ―Emerging Ethnic Minority Sub-cultures: young Tamils in the Post-war
Context in the Tamil-dominated Areas in Sri Lanka‖. Ethnic and Racial
Studies, vol. 43, no. 10, 2020, h. 1909-1928.
Anwar, D. F. ―Indonesia-China Relations: Coming Full Circle?. Southeast Asian
Affairs, no. 1, 2019, h. 145-161.
Anzola, D. & Rodríguez-Cárdenas, D. ―A Model of Cultural Transmission by
Direct Instruction: An Exercise on Replication and Extension‖. Cognitive
Systems Research, vol. 52, 2018, h. 450-465.
Arifani, Anif. ―Model Pengembangan Dakwah Berbasis Budaya Lokal‖, Jurnal
Ilmu Dakwah, vol. 4, no. 15, 2010, h. 849-878.
Arnason, J. P. ―Civilization, Culture and Power: Reflections on Norbert Elias'
Genealogy of the West‖. Thesis Eleven, vol. 24, no. 1, 1989, h. 44-70.
Asfari, A. & Askar, A. ―Understanding Muslim Assimilation in America: An
Exploratory Assessment of First & Second-Generation Muslims Using
Segmented Assimilation Theory‖. Journal of Muslim Minority Affairs, 2020, h.
1-18.
Attias-Donfut, C. ―Family transfers and cultural transmissions between three
generations in France‖. Global Aging and Challenges to Families, 2003, h.
214-252.
Aziz, Abdul, dkk. ―Pengelolaan Taman Wisata Goa Sunyaragi‖. Al-Musthofa:
Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, vol. 3, no. 1, 2018, h. 134-152.
Azra, Azyumardi, disampaikan dalam Webinar yang diselenggarakan PPIM Jakarta,
19 Juni 2020.
Azra, Azyumardi. ―The Indies Chinese and the Sarekat Islam: An account of the
Anti-Chinese Riots in Colonial Indonesia‖. Studia lslamika, vol. 1, no. 1, 1994,
h. 25-54.
Babb, L. A. ―Mirrored Warriors: On the Cultural Identity of Rajasthani
Traders‖. International Journal of Hindu Studies, vol. 3, no. 1, 1999, h. 1-25.
229
Bar-Gill, S. & Fershtman, C. ―Integration Policy: Cultural Transmission with
Endogenous Fertility‖. Journal of Population Economics, vol. 29, no. 1, 2016,
h. 105-133.
Barroso, C. S., Springer, A. E., Ledingham, C. M. & Kelder, S. H. ―A Qualitative
Analysis of the Social And Cultural Contexts that Shape Screen Time Use in
Latino Families Living on the US-Mexico Border‖. International Journal of
Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 15, no. 1, 2020, h. 1735766.
Benhabib, J. & Spiegel, M. M. ―Human capital and technology diffusion‖.
In Handbook of Economic Growth, vol. 1, 2015, h. 935-966.
Berray, M. ―A Critical Literary Review of the Melting Pot and Salad Bowl
Assimilation and Integration Theories‖. Journal of Ethnic and Cultural
Studies, vol. 6, no. 1, 2019, h. 142-151.
Berry, J. W. ―Acculturation and Adaptation in a New Society‖. International
Migration, vol. 30, 1992, h. 69-69.
Berry, J. W. ―Acculturation: Living successfully in Two Cultures‖. International
Journal of Intercultural Relations, vol. 29, no. 6, 2005, h. 697-712.
Berry, J. W. ―Achieving a Global Psychology‖. Canadian Psychology, vol. 54, no.
1, 2013, h. 55.
Berry, J. W. ―Cross‐cultural Psychology: A Symbiosis of Cultural and Comparative
Approaches‖. Asian Journal of Social Psychology, vol. 3, no. 3, 2000, h. 197-
205.
Berry, J. W. ―Globalisation and Acculturation‖. International Journal of
Intercultural Relations, vol. 32, no. 4, 2008, h. 328-336.
Berry, J. W. ―Immigration, Acculturation, and Adaption‖. Applied Psychology, An
International Review, vol. 46, 1997, h. 5-68.
Berry, J. W., Kim, U., Power, S., Young, M. & Bujaki, M. ―Acculturation Attitudes
in Plural Societies‖. Applied Psychology, vol. 38, no. 2, 1989, h. 185-206.
Berumen, F. C. ―Resisting Assimilation to the Melting Pot‖. Journal of Culture and
Values in Education, vol. 2, no. 1, 2019, h. 81-95.
Bhawuk, D. P. ―The Role of Culture Theory in Cross-cultural Training: A
Multimethod Study of Culture-specific, Culture-general, and Culture Theory-
based Assimilators‖. Journal of Cross-cultural Psychology, vol. 29, no. 5,
1998, h. 630-655.
Bi, L., Ehrich, J. & Ehrich, L. C. ―Confucius as Transformational Leader: Lessons
for ESL Leadership‖. International Journal of Educational Management, vol
26, no. 4, 2012, 391-402.
Boas, F. ―History and Science in Anthropology: A Reply‖. American
Anthropologist, vol. 38, no. 1, 1936, h. 137-141.
Boroch, R. ―A Formal Concept of Culture in the Classification of Alfred L. Kroeber
and Clyde Kluckhohn‖. Analecta, vol. 25, no. 2, 2016.
Brandes, J. L. A. ―Eenige Officiele Stukken met Betrekking tot
Tjirebon‖. TBG, vol. 37, 1894, h. 449-488.
Brons, A., Oosterveer, P., & Wertheim-Heck, S. ―Feeding the Melting Pot:
Inclusive Strategies for the Multi-ethnic City‖. Agriculture and Human Values,
2020, h. 1-14.
230
Brown, L. E. ―Cold War, Culture Wars, War on Terror: the NEA and the art of
public diplomacy‖. Cold War History, 2020, h. 1-19.
Bucholc, M. ―Schengen and the Rosary‖ Historical Social Research/Historische
Sozialforschung, vol. 45, no. 171, 2020, h. 153-181.
Budi, B. S. ―Tjarita Purwaka Tjaruban Nagari (Sedjarah Muladjadi Tjirebon)
1972‖. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, no. 4, 2005,
h.1-8.
Budiono, G. & Vincent, A. ―Batik Industry of Indonesia: The Rise, Fall and
Prospects‖. Studies in Business & Economics, vol. 5, no. 3, 2010, h. 156-170.
Burhanudin, J. ―Converting Belief, Connecting People: The Kingdoms and the
Dynamics of Islamization in Pre-Colonial Archipelago‖. Studia Islamika, vol.
25, no. 2, 2018, h. 247-278.
Busbridge, R., Moffitt, B. & Thorburn, J. ―Cultural Marxism: Far-right Conspiracy
Theory in Australia‘s Culture Wars‖. Social Identities, 2020, h. 1-17.
Buseri, F. B. ―The Role of Chinese Ethnic in Spread of Islam in Indonesia‖.
In Proceeding of The International Seminar and Conference on Global Issues,
vol. 1, no. 1, 2015, h. 48-54.
Busro, B. & Qodim, H. ―Perubahan Budaya dalam Ritual Slametan Kelahiran di
Cirebon, Indonesia‖. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, vol. 14, no. 2, 2018,
h. 127-147.
Carey, P. ―Changing Javanese Perceptions of the Chinese Communities in Central
Java, 1755-1825‖. Indonesia, vol. 37, 1984, h. 1-47.
Chang, Y. ―The Ming Empire: Patron of Islam in China and Southeast-West
Asia‖. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, vol. 61,
no. 2, 1988, h. 1-44.
Chen, J. R. & Li, T. Y. ―Rhythmic Character Animation: Interactive Chinese Lion
Dance‖. In SIGGRAPH Sketches, 2005, h. 72.
Cole, N. L. ―What is the Meaning of Acculturation? Understanding Acculturation
and How it Differs from Assimilation‖. 2018.
Cullum, J. & Harton, H. C. ―Cultural evolution: Interpersonal Influence, Issue
Importance, and the Development of Shared Attitudes in College Residence
Halls‖. Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 33, no. 10, 2007, h.
1327-1339.
D. Hamdani, ―Cultural System of Cirebonese People: Tradition of Muludan in the
Kanoman Kraton Indonesian‖. Journal of Social Sciences, vol. 4, no. 1, 2012
11-22.
Daniel, C. ―Language Policies, Immigrant Assimilation, and Minority Group
Advancement in the United States‖. In Handbook of the Changing World
Language Map, 2020, h. 2237-2259.
Daoshan, M. ―The Distribution and Feature Checking of Interrogative Sentences in
Tao Te Ching‖. Linguistics, vol. 4, no. 6, 2016, h. 230-236.
Darheni, N. ―The Language Characteristic and Its Acculturation from Chinese
Speakers in Losari, Cirebon Regency, West Java: The Acculturation of
Chinese with Javanese Culture‖. In The 1st International Seminar on
Language, Literature and Education, KnE Social Sciences, 2018, h. 663-686.
231
Dato-on, M. C. ―Cultural Assimilation and Consumption Behaviors: A
Methodological Investigation‖. Journal of Managerial Issues, 2000, h. 427-
445.
Daud, Ilyas. ―Surga di dalam Hadis‖. Farabi: Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang
Filsafat dan Dakwah, vol. 18. no. 2, 2018, h. 1-13.
Dawis, A. ―Chinese Education in Indonesia: Developments in the Post-1998
Era‖. Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia, 2008, h. 75-96.
Deviani, F. T. ―Perjanjian 7 Januari 1681 dan Implikasinya Terhadap Kehidupan
Sosial Politik Ekonomi di Kerajaan Cirebon (1681 M-1755 M)‖. Tamaddun,
vol. 4, no. 1, 2016, h. 123-146.
Dewey, J. ―Peirce's Theory of Linguistic Signs, Thought, and Meaning‖. The
Journal of Philosophy, vol. 43, no. 4, 1964, h. 85-95.
Dewi, H. I. dan Anisa, ―Akulturasi Budaya pada Perkembangan Kraton Kasepuhan
Cirebon‖. Proceeding PESAT Universitas Gunadarma Depok, vol. 3, 2009.
Diehl, C. ―Assimilation without groups?. Ethnic and Racial Studies, vol. 42, no. 13,
2019, h. 2297-2301.
Diprose, R. & Azca, M. N. ―Conflict Management in Indonesia‘s Post-authoritarian
Democracy: Resource Contestation, Power Dynamics and
Brokerage‖. Conflict, Security & Development, vol. 20, no. 1, 2020, h. 191-
221.
Djajadiningrat, P. H. ―Kanttekeningen bij, Het Javaanse rijk Tjerbon in de eerste
eeuwen van zijn bestaan‖. (Nr. 1487). Bijdragen tot de taal-, land-en
volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia,
vol. 113, no. 4, 1957, h. 380-392.
Djakfar, M. ―Corporate Social Responsibilty: Aktualisasi Ajaran Ihsan dalam
Bisnis‖. Ulul Albab, vol 11, no. 1, 2010, h. 111-130.
Dorian, J. P., Wigdortz, B. & Gladney, D. ―Central Asia and Xinjiang, China:
Emerging Energy, Economic and Ethnic Relations‖. Central Asian Survey, vol.
16, no. 4, 1997, h. 461-486.
Emalia, Imas. ―Geliat Ekonomi Kelas Menengah Muslim di Cirebon: Dinamika
Industri Batik Trusmi 1900-1980‖. Al-Turas, vol. XXIII, no. 2, 2017, h. 211-
230.
Erwantoro, H. ―Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon‖. Patanjala, vol. 4, no. 1, 2012,
h. 166-179.
Evans, R. ―Interpreting family struggles in West Africa across Majority-Minority
world Boundaries: Tensions and Possibilities‖. Gender, Place & Culture, vol.
27, no. 5, 2020, h. 717-732.
Fakhruddin, ―Eksistensi Syahadat dan Shalawat dalam Prespektif Tarekat Asy-
Syahadatain‖. Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan,
vol. 4, no. 2, 2018, h. 242-267.
Fang, Tony. ―Yin Yang: A new perspective on culture‖. Management and
organization Review, vol. 8, no. 1, 2012, h. 25-50.
Fauzan, M. ―Selubung Historiografi Syekh Maulana Maghribi, Wonobodro‖. Jurnal
Penelitian, vol. 12, no. 2, 2015, h. 261-281.
Firth, Shirley. ―End-of-life: a Hindu view‖. The Lancet, vol. 366, no. 9486, 2005, h.
682-686.
232
Fitri, R. F. R. ―Simbol Bangunan pada Komplek Gapura, Masjid dan Makam
Sendang Duwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa
Timur‖. Jurnal Penelitian, Universitas Airlangga, 2018, h. 1-10.
Foltarz, A. ―Symbols, Signs, Messages in Ergonomics of Social Space‖. Human-
Centered Computing: Cognitive, Social, and Ergonomic Aspects, vol. 3, 2019,
h. 200.
Fournié, Pierre. ―Rediscovering the Walisongo, Indonesia: A Potential New
Destination for International Pilgrimage‖. International Journal of Religious
Tourism and Pilgrimage, 7, no. 4, 2019, h. 77-86.
Freed, S. A. & Freed, R. S. ―Clark Wissler and the Development of Anthropology
in the United States‖. American Anthropologist, vol. 85, no. 4, 1983, h. 800-
825.
Freedman, A. ―Political Institutions and Ethnic Chinese Identity in
Indonesia‖. Asian Ethnicity, vol. 4, no. 3, 2003, h. 439-452.
Futaqi, Sauqi. ―Konstruksi Moderasi Islam (Wasathiyyah) dalam Kurikulum
Pendidikan Islam‖. In 2nd Proceedings; Annual Conference for Muslim
Scholars, UIN Sunan Ampel Surabaya, 21-22 April 2018, h. 521-530.
Ghazali, S., Mapjabil, J., Nor, A., Samat, N. & Jaafar, J. ―Difusi Ruangan Budaya
Transeksualisme dan Imaginasi Geografi Pelajar Lelaki Berpenampilan Silang
di Universiti Tempatan Malaysia‖. E-Bangi Journal of Social Science and
Humanities, vol. 7, no. 1, 2012, h. 252-266.
Gong, X. ―The Belt & Road Initiative and China‘s influence in Southeast
Asia‖. The Pacific Review, vol. 32, no. 4, 2019, h. 635-665.
Gottdiener, M. ―Hegemony and Mass Culture: A semiotic approach‖. American
Journal of Sociology, vol. 90, no. 5, 1985, h. 979-1001.
Gu, Chien-Juh. ―Qualitative Interviewing in Ethnic-Chinese Contexts: Reflections
From Researching Taiwanese Immigrants in the United States‖. International
Journal of Qualitative Methods, vol. 19, 2020.
Guoqing, Y. ―History of Taoism‖. Rituals and Practices in World Religions: Cross-
Cultural Scholarship to Inform Research and Clinical Contexts, vol. 5, 2019,
h. 99-112.
Gürpinar, G. ―Foreign Policy as a Contested Front of the Cultural Wars in
Turkey‖. Uluslararası İlişkiler/International Relations, vol. 17, no. 65, 2020,
h. 3-21.
Haake, A. ―The Role of Symmetry in Javanese Batik Patterns‖. Computers &
Mathematics with Applications, vol. 17, no. 4-6, 1989, h. 815-826.
Habibi, H. ―Protecting National Identity Based on the Value of Nation Local
Wisdom‖. International Journal of Malay-Nusantara Studies, vol. 1, no. 2,
2018, h. 24-40.
Hadinoto, ―Lingkungan Pecinan dalam Tata Ruang Kota di Jawa Pada Masa
Kolonial‖, dalam Mahdun, ―Konflik Cina-Pribumi dan Dampaknya Bagi
Pertumbuhan Industri Batik di Trusmi 1948‖. Jurnal Tamaddun, vol. 5, no. 2,
2017, h. 76-93.
Hanapi, Mohd Shukri. ―The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic
Epistemology: A Case Study of its Implementation in Malaysia‖. In
233
International Journal of Humanities and Social Science, vol. 4, no. 9, 2014, h.
51-62.
Hanggara, A. ―Nasionalisme Etnis Tionghoa di Indonesia‖. Jurnal Equilibrium, vol.
14, no. 02, 2016, h. 71.
Hannigan, T. P. ―Traits, Attitudes, and Skills that are Related to Intercultural
Effectiveness and their Implications for Cross-cultural Training: A Review of
the Literature‖. International Journal of Intercultural Relations, vol. 14, no. 1,
1990, h. 89-111.
Hao, L. ―Goodness: The Ultimate Integration of Confucianism, Buddhism and
Taoism in China‖. In Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy,
vol. 12, 2018, h. 143-147.
Hardwick, P. A. ―Horsing around Melayu: Kuda kepang, Islamic piety, and identity
politics at play in Singapore‘s Malay community‖. Journal of the Malaysian
Branch of the Royal Asiatic Society, vol. 87, no. 306, 2014, h. 1-19.
Hariadi, Y., Lukman, M. & Haldani, A. ―Batik Fractal: From Traditional Art to
Modern Complexity‖. In Proceeding Generative Art X Milan Italia, 2007, h. 1-
10.
Hariyanto, O. I. ―The Meaning of Offering Local Wisdom in Ritual Panjang
Jimat‖. International Journal of Scientific & Technology Research, vol. 6, no.
6, 2017.
Hariyati, N. ―Islamic Education in the Prespective of Islamic Nusantara‖.
In International Conference on Language, Education, Economic and Social
Science, vol. 1, no. 1, 2019, h. 125-134.
Hasanah, A., Gustini, N. & Rohaniawati, D. ―Cultivating Character Education
Based on Sundanese Culture Local Wisdom‖. Jurnal Pendidikan Islam, vol. 2,
no. 2, 2016, h. 231-253.
Hasiah, ―Mengintip Prilaku Sombong dalam Al-Quran‖. Jurnal El-Qanuny, vol. 4,
no. 2, 2018, h. 185-200.
Hassan, ―Islamic tourism: The Concept and the Reality‖. Islamic Tourism, vol. 14,
no. 2, 2004, h. 35-45.
Hassan, F. ―A Comparative Approach to Common Ground between Buddhism and
Islam‖. European Journal of Scientific Research, vol. 71, no. 4, 2012, h. 514-
519.
Hattenhauer, D. ―The Rhetoric of Architecture: A Semiotic
Approach‖. Communication Quarterly, vol. 32, no. 1, 1984, h. 71-77.
Hayhoe, R. ―Encountering Chinese Culture Over Changing Times‖. Education
Journal, vol. 47, no. 2, 2019, h. 1-22.
Hedges, S. ―Interior Decoration to Exterior Surface: The Beleaguered
Relief‖. Interiority, vol. 2, no. 1, 2019, h. 79-93.
Heidhues, M. S. ―Studying the Chinese in Indonesia: A long half-
century‖. SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia, vol. 32, no. 3,
2017, h. 601-633.
Hendro, E. P. ―Perkembangan Morfologi Kota Cirebon dari Masa Kerajaan Hingga
Akhir Masa Kolonial‖. Paramita, vol. 24, no. 1, 2014, h. 17-30.
Hermkens, A. K. ―Gendered Objects: Embodiments of Colonial Collecting in Dutch
New Guinea‖. The Journal of Pacific History, vol. 42, no. 1, 2007, h. 1-20.
234
Herskovits, M. J. ―The Significance of the Study of Acculturation for
Anthropology‖. American Anthropologist, vol. 39, no. 2, 1937, h. 259-264.
Herwiratno, M. ―Kelenteng: Benteng Terakhir dan Titik Awal Perkembangan
Kebudayaan Tionghoa di Indonesia‖. Lingua Cultura, vol. 1, no. 1, 2007, h.
78-86.
Hilmy, Masdar. ―Whither Indonesia‘s Islamic Moderatism? A reexamination on the
moderate vision of Muhammadiyah and NU‖. Journal of Indonesian
Islam, vol. 7, no. 1, 2013, h. 24-48.
Himatul Istiqomah dan Muhammad Ihsan Sholeh, ―The Concept of Buraq in The
Events of Isra Mi‘raj: Literature and Physics Perspective‖. AJIS: Academic
Journal of Islamic Studies, vol. 5, no. 1, 2020, h. 53-67.
HK, Aditya A. Putri & Soetejab, Zakarias S. ―Analysis of the Meaning of
Ciwaringin Batik Motifs Cirebon‖. The International Seminar QUOVADIS of
Traditional Arts XIII “Diversity in Culture”, 2017, h. 1-8.
HK, Aditya A. Putri & Wulandari, Desi. ―Analisis Makna Motif Batik Ciwaringin
Cirebon‖. Seminar Nasional Seni dan Desain: Reinvensi Budaya Visual
Nusantara, Jurusan Seni Rupa dan Jurusan Desain Universitas Negeri
Surabaya, 2019, h. 35-40.
Hoadley, M. C. ―Javanese, Peranakan, and Chinese Elites in Cirebon: Changing
Ethnic Boundaries.‖ The Journal of Asian Studies, vol. 47, no. 3, 1988, h. 503-
517.
Hodgson, G. ―Keris Types and Terms‖. Journal of the Malayan Branch of the Royal
Asiatic Society, vol. 29, no. 4. 176, 1965, h. 68-90.
Hoebel, E. A. ―Anthropology in Education‖. Yearbook of Anthropology, 1955, h.
391-395.
Hoebel, E. A. ―Karl Llewellyn: Anthropological Jurisprude‖. Rutgers Law
Review, vol. 18, 1963, h. 735.
Hoon, C. Y. ―Assimilation, multiculturalism, hybridity: The dilemmas of the ethnic
Chinese in post-Suharto Indonesia‖. Asian Ethnicity, vol. 7, no. 2, 2006, h.
149-166.
Houser, N. ―Toward a Peircean Semiotic Theory of Learning‖. The American
Journal of Semiotics, vol. 5 no. 2, 2008, h. 251-274.
Howard, M. C., ―Dress and ethnic identity in Irian Jaya‖. Journal of Social Issues in
Southeast Asia, 2000, h. 1-29.
Hubley, C., Hayes, J., Harvey, M., & Musto, S. ―To the victors go the existential
spoils: The mental-health benefits of cultural worldview defense for people
who successfully meet cultural standards and valued goals‖. Journal of Social
and Clinical Psychology, vol. 39, no. 4, 2020, h. 276-314.
Humaedi, M. A. ―Budaya Hibrida Masyarakat Cirebon‖. Humaniora, vol. 25, no. 3,
2013, h. 281-285.
Ibrahim, A. ―Islam in Southeast Asia‖. Ar Raniry: International Journal of Islamic
Studies, vol. 5, no. 1, 2018, h. 40-52.
Iliopoulos, A. ―Early body ornamentation as Ego-culture: Tracing the co-evolution
of aesthetic ideals and cultural identity‖. Semiotica, no. 232, 2020, h. 187-233.
235
Imamuddin, S. M. ―Arab Mariners and Islam in China (Under the Tang Dynasty
618-906 AC)‖. Journal of the Pakistan Historical Society, vol. 32, no. 3, 1984,
h. 155.
Indika, D. R. ―Ingsun Titip Tajug Lan Fakir Miskin‖, dalam Pembangunan dengan
Berbasiskan Budaya dan Kearifan (Pengembalian Citra Keraton sebagai
Pusat Kebudayaan dan Ekonomi Cirebon, ISEI Economic Review, vol II, no. 1,
2018, h. 1-7.
Iryana, Wahyu. ―Perjuangan Rakyat Cirebon-Indramayu Melawan Imperialisme‖.
At-Tsaqafah, vol. 17, no. 2, 2020, h. 373-381.
Islam, M. ―Data Analysis: Types, Process, Methods, Techniques and Tools‖.
International Journal on Data Science and Technology, vol. 6, no. 10, h. 2020.
Ismail, Ahmad Munawar. ―Aqidah as a Basic Of Social Toleranca: The Malaysian
Experience‖. International Journal of Islamic Thought, vol. 1, 2012, h. 1-7.
Ismail, K. ―Imperialism, Colonialism and their Contribution to the Formation of
Malay and Chinese Ethnicity: An Historical Analysis‖. Intellectual
Discourse, vol. 28, no. 1, 2020, h. 171-193.
Jacobsen, M. ―Islam and Processes of Minorisation among Ethnic Chinese in
Indonesia: Oscillating between Faith and Political Economic Expediency‖.
Asian Ethnicity, vol. 6, no. 2, 2005, h. 71-87.
Jaeger, Stefan. ―A geomedical approach to chinese medicine: the origin of the Yin-
Yang symbol‖. Recent Advances in Theories and Practice of Chinese
Medicine, 2012, h. 29-44.
Jaelani, A. ―Cirebon as the Silk Road: A New Approach of Heritage Tourisme and
Creative Economy‖. Journal of Economics and Political Economy (JEPE), vol.
3, no. 2, 2016, h. 264-283.
Jaelani, A., Setyawan, E. dan Nursyamsudin, ―Religi, Budaya Dan Ekonomi
Kreatif: Prospek dan Pengembangan Pariwisata Halal di Cirebon‖. Al-
Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, vol. 2, no. 2, 2017, h.
101-122.
Jahangir, J. S., ―Mappila Experience: Assimilation of Cultures and Legacy of Islam
in Kerala‖. Studies in Indian Place Names, vol. 40, no. 3, 2020, h. 2540-2547.
Jiang, Xinyan. ―Chinese dialectical thinking—the yin yang model‖. Philosophy
Compass, vol. 8, no. 5, 2013, h. 438-446.
Joedawinata, A. ―Unsur-unsur Pemandu dan Kontribusinya dalam Peristiwa
Perwujudan Sosok Artefak Tradisional dengan Indikasiindikasi Lokal yang
Dikandung dan Dipancarkannya (Studi dalam Konteks Keilmuan Seni Rupa,
Kriya dan Desain dengan Cirebon dan Artefak Kriya Anyaman Wadah-
wadahan Sebagai Kasus)‖. ITB, 2005.
Kaliki, N. ―The Symbol of Traditional Cloths of Kabasaran Dance‖. Linguistic
Journal, vol. 6, no. 1, 2018, h. 30-40.
Kasdi, Abdurrohman. ―The Role of Walisongo in Developing the Islam Nusantara
Civilization‖. Addin, vol. 11, no. 1, 2017, h. 1-26.
Kavaler, E. M. ―Ornament and Systems of Ordering in the Sixteenth-Century
Netherlands‖. Renaissance Quarterly, vol. 72, no. 4, 2019, h. 1269-1325.
236
Khisni, A. & Handayani, I. G. A. K. R. ―The Transformation of Islamic Law Into
the National Legislation‖. Journal of Talent Development and Excellence, vol.
12, no. 2s, 2020, h. 1275-1281.
Kroeber, A. L. & Kluckhohn, C. ―Culture: A Critical Review of Concepts and
Definitions‖. Papers: Peabody Museum of Archaeology & Ethnology, Harvard
University, vol. 47, no. 1, 1952, h. viii.
Kumala, Olivia Dwi, dkk. ―Efektifitas Pelatihan Dzikir dalam Meningkatkan
Ketenangan Jiwa pada Lansia Penderita Hipertensi‖. Psympathic: Jurnal
Ilmiah Psikologi, vol. 4, no. 1, Juni 2017, h. 55-66.
Kuntjara, E. & Hoon, C. Y. ―Reassessing Chinese Indonesian stereotypes: two
decades after Reformasi‖. South East Asia Research, 2020, h. 1-18.
Kuo, H. Y. ―South Seas Chinese in Colonial‖. Framing Asian Studies: Geopolitics
and Institutions, 2018, h. 231.
Kurniadi, E. ―Structuralism Approach: Symbolism of Traditional Batik Pattern of
Javanese Traditional Clothes In Surakarta‖. In 3rd International Conference on
Creative Media, Design and Technology (REKA 2018), (Atlantis Press, 2018).
Kurnianto R. & Lestarini, N. ―Integration of Local Wisdom in Education‖.
In International Seminar on Education, 2020, h. 557-563.
Kurniawan, H. ―Ethnic Chinese during the New Order: Teaching Materials
Development for History Learning based on Multiculturalism‖. Paramita:
Historical Studies Journal, vol. 30, no. 1, 2020, h. 46-54.
Kurniawan, H. ―The Role of Chinese in Coming of Islam to Indonesia: Teaching
Materials Development Based on Multiculturalism‖. Paramita: Historical
Studies Journal, vol. 27, no. 2, 2017, h. 238-248.
Kustedja, Sugiri, dkk. ―Feng-Shui: Elemen Budaya Tionghoa Tradisional‖.
Melintas, vol 28, no. 1. 2012, h. 61-89.
Kustedja, Sugiri, dkk. ―Makna Ikon Naga, Long, Elemen Utama Arsitektur
Tradisional Tionghoa‖. Jurnal Sosioteknologi, ed. 30, thn. 12, 2013, h. 526-
539.
Larkin, B., Meyer, B. & Akyeampong, E. K. ―Pentecostalism, Islam &
Culture‖. Themes in West Africa's History, 2006, h. 286-312.
Larsen, T. ―EB Tylor, Religion and Anthropology‖. The British Journal for the
History of Science, 2013, h. 467-485.
Lasmiyati, ―Keraton Kanoman di Cirebon (Sejarah dan Perkembangannya)‖.
Patanjala, vol. 5, no. 1, 2013, h. 131-146.
Laufer, B. ―Post Scriptum‖. In F. C. Cole, Chinese Pottery in the Philippines, Field
Museum of Natural History, Anthropological Series, vol. XII, no. 1, 1912.
Lawrence, R. K., Edwards, M., Chan, G. W., Cox, J. A. & Goodhew, S. C. ―Does
Cultural Background Predict the Spatial Distribution of Attention?. Culture
and Brain, 2019, h. 1-29.
Lee, J. ―Promoting Majority Culture and Excluding External Ethnic Influences:
China‘s Strategy for the UNESCO ‗intangible‘cultural heritage list. Social
Identities, vol. 26, no. 1, 2020, h. 61-76.
Leijten, J. ―Mauro Jambi, the Capital of Srivijaya: According to the writings of I-
Tsing, Chau Ju-kua and Resent‖. Studies and Archaeological Findings, 2017,
h. 1-44.
237
Lestari, S. N. & Wiratama, N. S. ―The dark side of the Lasem maritime industry:
Chinese power in opium business in the XIX century‖. Journal of Maritime
Studies and National Integration, vol. 2, no. 2, 2018, h. 91-100.
Li, M. ―Performing Chineseness: The Lion Dance in Newfoundland‖. Asian
Ethnology, vol. 76, no. 2, 2017, h. 289-317.
Liang, H. ―Jung and Chinese Religions: Buddhism and Taoism‖. Pastoral
Psychology, vol. 61, no. 5-6, 2012, h. 747-758.
Lievander, David., Olivia, dan Chun-I, Kuo. ―Ritual Perayaan Imlek Etnis Tionghoa
Di Kota Toli-toli‖. Century: Journal of Chinese Language, Literature and
Culture, vol. 5, no. 1, 2017, h. 10-17.
Lim, L. Y. ―Southeast Asian Chinese business: Past success, recent crisis and future
evolution‖. Business, Government and Labor: Essays on Economic
Development in Singapore and Southeast Asia, 2017, h. 313.
Linton, R. The Study of Man: An Introduction, (Appleton-Century, 1936).
Lissoni, F. ―International Migration and Innovation Diffusion: An Eclectic
Survey‖. Regional Studies, vol. 52, no. 5, 2018, h. 702-714.
Lizardo, O. ―Simmel‘s Dialectic of Form and Content in Recent Work in Cultural
Sociology‖. The Germanic Review: Literature, Culture, Theory, vol. 94, no. 2,
2019, h. 93-100.
Lobja, E., Umaternate, A., Pangalila, T., Karwur, H. & Burdam, Y. ―The
Reconstruction of Cultural Values and Local Wisdom of the Tombulu Sub-
Ethnic of Minahasa Community in the Walian Village of Tomohon City‖.
In International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019), (Atlantis
Press, 2019).
Lombard, D. & Salmon, C. ―Islam and Chineseness‖. Indonesia, no. 57, 1993, h.
115-131.
Lombard, D. ―H. J. de Graaf & Th. G. Th. Pigeaud, Chinese Muslims in Java in the
15th and 16th Centuries‖. Archipel, vol. 32, no. 1, 1986, h. 186-187.
Lombard, D. ―Jardins à Java‖. Arts Asiatiques, vol. 20, 1969, h. 135-183.
Lone, M. A. ―Towards A Sociology of Assimilation: Concept, Theory, Debate and
Practice in Cultural Anthropology‖. Asian Journal of Research in Social
Sciences and Humanities, vol. 3, no. 12, 2013, h. 131-166.
Lubis, N. H., Sulaeman, A., Munaf, Y. & M. R. Razman, ―Islamization of the
Sunda Kingdom‖. International Information Institute (Tokyo),
Information, vol. 21, no. 4, 2018, h. 1349-1357.
Lubis, S. & Buana, R. ―Stereotypes and Prejudices in Communication between
Chinese Ethnic and Indigenous Moslem in Medan City, North Sumatra
Province–Indonesia‖. Britain International of Humanities and Social Sciences
(BIoHS) Journal, vol. 2, no. 2, 2020, h. 513-522.
Made, J. E. ―Sacrifice in African Traditional Religion: Differential Faith Issues in
Religions‖. Journal of Religion and Human Relations, vol. 8, no. 1, 2016, h.
20-35.
Mahfud, C. ―The Role of Cheng Ho Mosque: The New Silk Road, Indonesia-China
Relations in Islamic Cultural Identity‖. Journal of Indonesian Islam, vol. 8, no.
1, 2014, h. 23-38.
238
Majchrzyk, Z. ―Cultural Identity and Aggression within the Acculturation
Framework of the Global World‖. Sveikatos, vol. 29, no. 1, 2019, h. 56.
Manalu, H. P. ―Adat Batak Ditinjau dari Perspektif Iman Kristen‖. Haggadah,
vol. 1, no. 1, 2020, h. 32-41.
Marett, R. R. ―Presidential Address. The Transvaluation of Culture‖. Folklore, vol.
29, no. 1, 1918, h. 15-33.
Marrison, G. E. ―The coming of Islam to the East Indies‖. Journal of the Malayan
Branch of the Royal Asiatic Society, vol. 24, no. 1, 1951, h. 28-37.
Masduqi, Z. ―Penggunaan Dinar-Dirham dan Fulus: Upaya Menggali Tradisi yang
Hilang (Studi Kasus di Wilayah Cirebon)‖. Holistik, vol. 13, no. 2, 2012.
Maulana, R. ―Dakwah dan Etnisitas: Negosiasi Identitas pada Majalah Cheng
Hoo‖. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, vol. 19, no. 1, 2013, h. 25-39.
McCole, J. ―Georg Simmel: Decentering the Self and Recovering Authentic
Individuality‖. The Germanic Review: Literature, Culture, Theory, vol. 94, no.
2, 2019, h. 151-162.
McGuire, C. ―The Rhythm of Combat: Understanding the Role of Music in
Performances of Traditional Chinese Martial Arts and Lion Dance‖.
MUSICultures, vol. 42, no. 1, 2015, h. 2-23.
Mennell, S. & Rundell, J. ―Introduction: Civilization, Culture and the Human Self-
image‖. In Classical Readings on Culture and Civilization, (Routledge, 2017).
Min, Li. ―The Trans-Pacific Extension of Porcelain Trade in the Early Modern Era:
Cultural Transformations Across Pacific Space‖. In P. K. Cheng (ed.),
Proceeding of the International Symposium: Chinese Export Ceramics in the
16th and 17th Centuries and the Spread of Material Civilisation, (Hong Kong:
The City University, 2012).
Ming-ze, Y. U. A. N. ―A Survey on the Relationship History between Buddhism
and Taoism in Southeast Guangxi‖. Journal of Yulin Normal University, no. 1,
2016, h. 5.
Monica, ―Feng Shui dalam Mendesain Logo‖. Humaniora, vol. 2, no. 1, 2011, h.
132-138.
Muas, T. E. ―Restoring Trusts without Losing Face: An Episode in the History of
China–Indonesia Relationship‖. Tawarikh, vol. 6, no. 2, 2015.
Muchomba, F. M., Jiang, N. & Kaushal, N. ―Culture, labor supply, and fertility
across immigrant generations in the United States‖. Feminist Economics, vol.
26, no. 1, 2020, h. 154-178.
Muffid, Mudhofar, dkk. ―Konsep Arsitektur Jawa dan Sunda pada Masjid Agung
Sang Cipta Rasa Cirebon‖. Modul , vol. 14, no. 2, 2014, h. 65-70.
Mulyono, ―Keistimewaan Istiqomah dalam Perspektif Al-Quran‖. Imtiyaz, vol. 4,
no. 01, 2020, h. 1-15.
Mulyono, Grace dan Thamrin, Diana. ―Makna Ragam Hias Binatang pada Klenteng
Kwan Sing Bio di Tuban‖. Dimensi Interior, vol. 6, no. 1, 2008, h. 1-8.
Mustajab, Ali. ―Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia‖.
IN RIGHT, vol. 5, no. 1, 2015, h. 153-193.
Muzakki, A. ―Ethnic Chinese Muslims in Indonesia: An Unfinished Anti-
Discrimination Project‖. Journal of Muslim Minority Affairs, vol. 30, no. 1,
2010, h. 81-96.
239
Muzzaki, A. ―Cheng Hoo Mosque: Assimilating Chinese Culture, Distancing it
from the State‖. London, UK: Crise Working Paper, no. 71, 2010, h. 1-29.
Narawati, T. ―Arts and Design Education for Character Building‖. In International
Conference on Arts and Design Education (ICADE 2018), (Atlantis Press,
2019).
Nawyn, S. J. & Park, J. ―Gendered segmented assimilation: earnings trajectories of
African immigrant women and men‖. Ethnic and Racial Studies, vol. 42, no. 2,
2019, h. 216-234.
Nettle, D. ―Selection, Adaptation, Inheritance and Design in Human Culture: The
view from the Price Equation‖. Philosophical Transactions of the Royal
Society, vol. 375, no. 1797, 2020, h. 20190358.
Ngafifi, M. ―Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial
Budaya‖. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, vol. 2, no.
1, 2014, h. 33-47.
Nowak, M. ―The Funnel Beaker Culture in Western Lesser Poland: Yesterday and
Today‖. Archaeologia Polona, vol. 57, 2019.
Nurhidayat, M. & Herlambang, Y. ―Visual Analysis of Ornament Kereta Paksi
Naga Liman Cirebon‖. Bandung Creative Movement Journal, vol. 4, no. 2,
2018.
Nursalim, A. & Sulastianto, H. ―Dekonstruksi Motif Batik Keraton Cirebon:
Pengaruh Ragam Hias Keraton pada Motif Batik Cirebon‖. Jurnal Penelitian
Pendidikan, vol. 15, no. 1, 2016, h. 27-40.
Nursalim, A. T., Rohidi, R., Triyanto, T. & Iswidiarti, S. ―Batik Wadasan Motif,
Past and Present‖. In Proceeding of International Conference on Art,
Language, and Culture, 2017. h. 215-225.
Nurudin, N. & Nurfalah, F. Communication Marketing of Youth and Sport
Department of Culture and Tourism in the Water Park Cave Sunyaragi Cirebon
City, West Java, Indonesia. In International Symposium on Social Sciences,
Education, and Humanities (ISSEH 2018), vol. 306, (Atlantis Press, 2019), h.
31-34.
Odewale, A. ―An Archaeology of Struggle: Material Remnants of a Double
Consciousness in the American South and Danish Caribbean
Communities‖. Transforming Anthropology, vol. 27, no. 2, 2019, h. 114-132.
Okoro, N. K. ―Oriental Traditions [Taoism]: A Critical Option for Peace Building
Initiative in the Contemporary Society‖. Journal of Social Research, vol. 1, no.
4. 2017.
Olson, K. E., O‘Brien, M. A., Rogers, W. A. & Charness, N. ―Diffusion of
Technology: Frequency of Use for Younger and Older Adults‖. Ageing
International, vol. 36, no. 1, 2011, h. 123-145.
Pakkanen, J., Brysbaert, A., Turner, D. & Boswinkel, Y. ―Efficient three-
dimensional field documentation methods for labour cost studies: Case studies
from archaeological and heritage contexts‖. Digital Applications in
Archaeology and Cultural Heritage, vol. 17, 2020, h. 1-10.
Parisi, D., Cecconi, F. & Natale, F. ―Cultural Change in Spatial Environments: the
Role of cultural assimilation and internal changes in cultures. Journal of
Conflict Resolution, vol. 47, no. 2, 2003, h. 163-179.
240
Parks, J. ―Defending the American Way of Life: Sport, Culture, and the Cold War
ed. by Toby C. Rider‖. Journal of Arizona History, vol. 60, no. 3, 2019, h. 388-
390.
Parmono, K. ―Simbolisme Batik Tradisional‖. Jurnal Filsafat, vol. 1, no. 1, 1995, h.
28-35.
Pathak, P. & Vadiya, S. ―Role of Employee Assimilation in Controlling Job
Hopping–An Empirical Study‖. Studies in Indian Place Names, vol. 40, no. 8,
2020, h. 297-307.
Patimah, Iin, dkk. ―Pengaruh Relaksasi Dzikir Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien
Gagal Ginjal Kronis yang Menjalani Hemodialisa‖. Jurnal Keperawatan
Padjajaran, vol. 3, no. 1, 2015, h. 18-24.
Patria, A. S. ―Dutch Batik Motifs: The Role of The Ruler and The Dutch
Bussinesman‖. Harmonia: Journal of Arts Research and Education, vol. 16,
no. 2, 2016, h. 125-132.
Pavlyshyn, L., Voronkova, O., Yakutina, M. & Tesleva, E. ―Ethical Problems
Concernig Dialectic Interaction of Culture and Civilization‖. Journal of Social
Studies Education Research, vol. 10, no. 3, 2019, h. 236-248.
Piliang, Y. A. ―Semiotik Teks: Sebuah Pendekatan Analisis Teks‖. Jurnal
Komunikasi, vol. 5, no. 2, 2004, h.189-198.
Pirazzoli-T‘Serstevens, M. ―Une Denrée Recherchée: la Céramique Chinoise
Importée dans le Golfe Arabo-persique, IXe–XIV
e Siècles‖. Mirabilia Asiatica,
vol. 2, 2005, h. 69-88.
Poerwanto, Hari. ―Asimilasi, Akulturasi, dan Integrasi Nasional‖. Humaniora, vol.
11, no. 3, 1999, h. 29-37.
Poerwanto, Hari. Orang Cina Khek dari Singkawang, (Depok: Komunitas Bambu).
Pope, C. & Allen, D. ―Observational Methods‖. Qualitative Research in Health
Care, 2020, h. 67-81.
Prima Yustana, ―Gajah dalam Terakota Majapahit‖. Jurnal Dewa Ruci, vol. 7, no. 1,
2011, h. 102-114.
Ptak, R. ―China and the Trade in Cloves, circa 960-1435‖. Journal of the American
Oriental Society, 1993, h. 1-13.
Purwati, E. & Rusydiyah, E. F. ―Transformative Islamic Education of Convert
Chinese Muslim‖. Journal of Talent Development and Excellence, vol. 12, no.
1, 2020, h. 164-178.
Putra, Bintang Hanggoro. ―Fungsi dan Makna Kesenian Barongsai bagi Masyarakat
Etnis Cina Semarang‖. Harmonia, vol. IX, no. 1, 2009, h. 1-11.
Qian, L. & Garner, M. ―A Literature Survey of Conceptions of the Role of Culture
in Foreign Language Education in China (1980–2014)‖. Intercultural
Education, vol. 30, no. 2, 2019, h. 159-179.
Queiroz, J. & Stjernfelt, F. ―Introduction: Peirce‘s Extended Theory and
Classifications of Signs‖. Semiotica, vol. 2019, no. 228, 2019, h. 1-2.
al Qurtuby, S. ―The Tao of Islam: Cheng Ho and the Legacy of Chinese Muslims in
Pre-Modern Java‖. Studia Islamika, vol. 15, no. 1, 2009, h. 51-78.
al Qurtuby, S. ―Islam di Tiongkok dan China Muslim di Jawa Pada Masa Pra-
Kolonial Belanda‖. Konfrontasi, vol. 1, no. 2, 2012, h. 69-90.
241
al Qurtuby, S. ―Melaka, Cheng Ho, dan Kesadaran Sejarah Kita‖, Malaysia,
Konferensi Internasional Bertajuk “Zheng He and Afro-Asian World”, 5
Januari 2014.
al Qurtuby, S. ―The Imprint of Zheng He and Chinese Muslims in Indonesia‘s
Past‖. Zheng He and the Afro-Asian World, h. 171-186.
Rachim, A. ―Al Adah Muhakkamah‖. Al-Mawarid Journal of Islamic Law, vol. 4,
1995, h. 8-13.
Rahma, A., Jaenudin, J. & Marifatullah, A. ―Living a Multicultural Lifestyle with
Batik: Identity, Representation, Significance‖. In International Conference on
Culture and Language in Southeast Asia (ICCLAS 2017), vol. 154, (Atlantis
Press, 2017).
Rahmat, Munawar. ―Manusia Menurut Alquran‖. Ta‟lim, vol. 10, no. 2, 2012, h.
105-122.
Rahmawati, R., Yahiji, K., Mahfud, C., Alfin, J. & Koiri, M. ―Chinese Ways of
Being Good Muslim: Fom the Cheng Hoo Mosque to Islamic Education and
Media Literacy‖. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, vol. 8, no.
2, 2018, h. 225-252.
Rasyidian, Firda, dkk. ―Spatial Principles and Ornamentsation on Water Garden
Relics of Kesultanan Cirebon: Case Student Witana Water Garden, Pakungwati
Water Garden, and Sunyaragi Water Garden‖. Jurnal Risa, vol. 03, no. 04,
2019, h. 363-380.
Ratnapalan, L. ―EB Tylor and the Problem of Primitive Culture‖. History and
Anthropology, vol. 19, no. 2, 2008, h. 131-142.
Ratnapuri, C. I. ―Chinese Ethnic Perspective on the Confucius Values of Leadership
in West Java Fuqing Organization‖. Pertanika Journal of Social Sciences &
Humanities, vol. 28, 2020.
Ratnawati, R., Syah, I. & Arif, S. ―Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia
tentang Dwikewarganegaraan Etnis Tionghoa pada Masa Demokrasi
Liberal‖. Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah, vo. 1, no. 1, 2013, h. 1-8.
Razi, Fahrur. ―NU dan Kontinuitas Dakwah Kultural‖. Jurnal Komunikasi Islam,
vol. 01, no. 02, 2011, h. 161-172.
Redfield, R., Linton, R. & Herskovits, M. J. ―Memorandum for the Study of
Acculturation‖. American Anthropologist, vol. 38, no. 1, 1936, h. 149-152.
Reid, A. ―The Structure of Cities in Southeast Asia, Fifteenth to Seventeenth
Centuries‖. Journal of Southeast Asian Studies, vol. 11, no. 2, 1980, h. 235-
250.
Ritter, W. ―Recreation and tourism in the Islamic countries‖. Ekistics, 1975, h. 56-
59.
Riyanti, M. T. & Rouselyn, M. ―The Influence of Art Motif Batik Mega Mendung
Cirebon to Fesyen in Jakarta‖. International Journal of Research of
Granthaalayah, vol. 6, no. 3, 2018, h. 107-125.
Rizaldi, D. ―Ethnic Chinese Social Assimilation in Cibadak Chinatown
Bandung‖. International Journal Pedagogy of Social Studies, vol. 3, no. 2,
2018, h. 133-141.
Rohman, A. ―Chinese–Indonesian Cultural and Religious Diplomacy‖. Journal of
Integrative International Relations, vol. 4, no. 1, 2019, h. 1-24.
242
Rohmanu, A. ―Acculturation of Javanese and Malay Islam in Wedding Tradition of
Javanese Ethnic Community at Selangor, Malaysia‖. KARSA: Journal of Social
and Islamic Culture, vol. 24, no. 1, 2016, h. 52-66.
Rokhani, U., Salam, A. & Rochani-Adi, I. ―Konstruksi Identitas Tionghoa melalui
Difusi Budaya Gambang Kromong: Studi Kasus Film Dikumenter Anak Naga
Beranak Naga‖. Resital: Jurnal Seni Pertunjukan (Journal of Performing
Arts), vol. 16, no. 3, 141-152.
Rokhman, M. N. & Yuliana, L. ―History Learning at Secondary School about
Demak Kingdom‖. Journal of Social Studies (JSS), vol. 14, no. 1, 2018.
Rose, J. & Johnson, C. W. ―Contextualizing Reliability and Validity in Qualitative
Research: Toward More Rigorous and Trustworthy Qualitative Social Science
in Leisure Research‖. Journal of Leisure Research, 2020, h. 1-20.
Rosmalia, Dini. ―Pola Ruang Lanskap Keraton Kasepuhan Cirebon‖. Prosiding
Semarnusa IPLBI ITS Surabaya, 2018, h. 074-082.
Rosyidin, D. N. ―Ulama Pasca Sunan Gunung Jati: Jaringan Intelektual Islam
Cirebon Abad ke-16 sampai dengan Abad ke-18‖. Jurnal Sosiologi Walisongo
(JSW), vol. 1, no. 2, 2017, h. 77-194.
Rudmin, F. W. ―Debate in Science: The Case of Acculturation‖, AnthroGlobe
Journal, 2006, h. 72-73.
Rukiah, Y. ―Visual Elements of Semar Calligraphy‖ on Cirebon Glass Painting of
Kusdono‘s Work‖. In International and Interdisciplinary Conference on Arts
Creation and Studies, vol. 1, 2019, h. 43-47.
Rusyanti, ―Peranan Tan Sam Cai Kong dalam Sejarah Cirebon‖. Purbawidya, vol.
2, no. 1, 2013, h. 105-117.
Rusyanti, The Role of Tan Sam Cai Kong in Cirebon History‖. Purbawidya, vol. 2,
no. 1, 2013, h. 105-117.
Saddhono, K. & Supeni, S. ―The Role of Dutch Colonialism in the Political Life of
Mataram Dynasty: A Case Study of the Manuscript of Babad Tanah
Jawi‖. Asian Social Science, vol. 10, no. 15, 2014, h. 1-7.
Safari, A. O. ―Perta Naskah Cirebon‖, Makalah Disampaikan dalam Forum Diskusi
Bulanan, Pusat Kajian Sejarah dan Budaya (PKSB) Jurusan Adab STAIN
Cirebon, 7 Maret 2009.
Saleebey, D. ―Culture, Theory, and Narrative: The Intersection of Meanings in
Practice‖. Social Work, vol. 39, no. 4, 1994, h. 351-359.
Salim, Polniwati. ―Memaknai Pengaplikasian Ornamen pada Atap Bangunan
Klenteng sebagai Ciri Khas Budaya Tionghoa‖. Aksen, vol 1, no. 2, 2016, h.
50-65.
Salisu, T. M. ―‗Urf/‗Adah (Custom): An Ancillary Mechanism in Shari ‗ah‖. Ilorin
Journal of Religious Studies, vol. 3, no. 2, 2013, h. 133-148.
Salmon, Claudine. ―The Chinese Community of Surabaya, from Its Origins to the
1930s Crisis‖. Chinese Southern Diaspora Studies, vol. 3, 2009, h. 23.
Sanusi, B. ―Jum‘atan in the Graveyard: An Anthropological Study of Pilgrims in the
Grave of Sunan Gunung Jati Cirebon, West Java‖. Journal of Indonesian
Islam, vol. 4, no. 2, 2010, h. 317-340.
Sapari, Rizal. ―Interaksi Simbolik dalam Tiga Lukisan Kaca Karya Haryadi Suadi‖.
Jurnal Itenas Rekarupa, vol. 5, no. 2, 2019, h. 107-114.
243
Sartini, Ni Wayan. ―Konsep dan Nilai Kehidupan Masyarakat Tionghoa: Analisis
Wacana Ritual Tahun Baru Imlek‖. Masyarakat Kebudayaan dan Politik, vol.
19, no. 2, 2006, h. 47-62.
Scholze, M. ―Trading Cultures: Berbers and Tuareg as Souvenir Vendors Marko
Scholze and Ingo Bartha‖. In Between Resistance and Expansion: Explorations
of Local Vitality in Africa, vol. 18, 2004, h. 69.
Schwartz, S. J., Unger, J. B., Zamboanga, B. L. & Szapocznik, J. ―Rethinking the
Concept of Acculturation: Implications for Theory and Research‖. American
Psychologist, vol. 65, no. 4, 2010, h. 237-251.
Secter, Mondo. ―The yin-yang system of ancient china: The yijing-book of changes
as a pragmatic metaphor for change theory‖. Journal for Interdisciplinary and
Cross-Cultural Studies, vol. 1, no. 1, 1998, h. 85-106.
Serour, G. I. ―Islamic Perspectives in Human Reproduction‖. Reproductive
Biomedicine Online, vol. 17, 2008, h. 34-38.
Setiani, Riris Eka. ―Pendidikan Seks Bagi Anak : Perspektif Al-Qur‘an”. Yinyang,
vol. 12, no. 1, 2017, h. 57-84.
Shabana, A. ―'Urf and'Adah within the Framework of Al-Shatibi's Legal
Methodology‖. UCLA J. Islamic & Near EL, vol. 6, 2006, h. 87.
Sheikh, S. Z. ―Persian Allegory of Chinoiserie Motifs-Dragon and Phoenix or
Simurgh‖. International Journal of Multidisciplinary and Current
Research, vol. 5, 2017.
Silong, L. ―Threes Types of Confluence among Confucianism, Buddhism and
Taoism‖. Journal of Peking University (Philosophy & Social Sciences), vol. 2,
2011.
Simons, S. E. ―Social Assimilation‖. American Journal of Sociology, vol. 6, no. 6,
1901, h. 790-822.
Sinaga, R., Tanjung, F. & Nasution, Y. ―Local Wisdom and National Integration in
Indonesia: A Case Study of Inter-Religious Harmony amid Social and Political
Upheaval in Bunga Bondar, South Tapanuli‖. Journal of Maritime Studies and
National Integration, vol. 3, no. 1, 2019, h. 30-35.
Smiraglia, R. P. ―Works as Signs, Symbols, and Canons: The Epistemology of the
Work‖. Ko Knowledge Organization, vol. 28, no. 4, 2001, h. 192-202.
Soegiarty, T. ―Ornamen Batik Pesisiran Daerah Sunda‖. Jurnal Dimensi Seni Rupa
dan Desain, vol. 13, no. 1, 2016, h. 23-38.
Soenarto, E. ―From Saints to Superheroes: The Wali Songo Myth in Contemporary
Indonesia's Popular Genres‖. Journal of the Malaysian Branch of the Royal
Asiatic Society, 2005, h. 33-82.
Soete, L. ―International Diffusion of Technology, Industrial Development and
Technological Leapfrogging‖. World Development, vol. 13, no. 3, 1985, h.
409-422.
Sofiyawati, N. ―Kajian Gaya Hias Singa Barong dan Paksi Naga Liman dalam
Estetila Hibriditas Kereta Kesultanan Cirebon‖. Jurnal Sosioteknologi, vol. 16,
no. 3, 2017, h. 304-324.
Sopiah, P. S. ―Inpres No 14 Tahun 1967 dan Implikasinya Terhadap Identitas
Muslim Tionghoa Cirebon‖. Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan
Kebudayaan Islam, vol. 5, no. 2, 2017, h. 152-173.
244
Spiller, H. J. ―Basic Gamelan Concepts in the Music of Cirebon‖. In Focus:
Gamelan Music of Indonesia, (Routledge, 2010).
Stenberg, J. ―From the (Tang) General to the (Jakarta) Specific: Xue Rengui across
Time and Space‖. Asian Studies Review, 2020, h. 1-19.
Stuart-Fox, M. ―Southeast Asia and China: The role of history and culture in
shaping future relations‖. Contemporary Southeast Asia: A Journal of
International and Strategic Affairs, vol. 26, no. 1, 2004, h. 116-139.
Su, W. ―Study on the Inheritance and Cultural Creation of Manchu Qipao Culture‖.
In 3rd International Conference on Art Studies: Science, Experience,
Education (ICASSEE 2019), (Atlantis Press, 2019).
Suardana, W. & Fikriyyati, I. ―Naga Liman Pencana Kencana Train Caruban
Nagari's Multicultural Symbols: Inculturalization of Nusantara Art in Cultural
Arts Education‖. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, vol. 24,
no. 2, 2020.
Sudardi, B. ―The Reflection of Socio-Cultural Change in Batik Motifs‖. In 2018 3rd
International Conference on Education, Sports, Arts and Management
Engineering (ICESAME 2018), vol. 231, (Atlantis Press, 2018).
Sudjarwo, S. & Pujiati, P. ―The Shifting Tradition of Ethnic Chinese Weddings at
Pecinan Village Bandar Lampung City‖. Research on Humanities and Social
Sciences, vol. 8, no. 12, 2018, h. 58-65.
Sumino, ―Kereta Singa Barong di Keraton Kasepuhan Cirebon‖. Corak: Jurnal Seni
Kriya, vol. 1, no. 1, 2012, h. 78-90.
Suneki, S. ―Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah‖. CIVIS, vol.
2, no. 1, 2012, h. 307-32.
Suparman, S., Sulasman, S. & Firdaus, D. ―Political Dynamics in Cirebon from the
17th to 19th Century‖. Tawarikh, vol. 9, no. 1, 2017, h. 49-58.
Supatmo, ―Keragaman Seni Hias Bangunan Bersejarah Masjid Agung Demak‖.
Imajinasi, vol. 10, 2, 2016, h. 107–120.
Supatmo, S. ―The Manifestation of Cultural Tolerance Value of Traditional
Ornament: Study on Ornaments of Sendang Duwur Mosque-Graveyard,
Lamongan, East Java‖. In 2nd International Conference on Arts and Culture
(ICONARC 2018), vol. 276, (Atlantis Press, 2019).
Suprajitno, S. ―Reconstructing Chineseness: Chinese Media and Chinese Identity in
Post-Reform Indonesia‖. Kemanusiaan: The Asian Journal of Humanities, vol.
27, no. 1, 2020.
Suryadi, M. ―Nilai Filosofis Peralatan Tradisional Terhadap Karakter Perempuan
Jawa dalam Pandangan Masyarakat Pesisir Utara Jawa Tengah‖. NUSA, vol.
13, no. 4, 2018, h. 567-578.
Suryadinata, L. ―Chinese Indonesians in Post-Suharto Indonesia: Democratisation
and Ethnic Minorities by Chong Wu-Ling‖. Sojourn: Journal of Social Issues
in Southeast Asia, vol. 35, no. 1, 2020, h. 165-168.
Suryadinata, L. ―Indonesian State Policy Towards Ethnic Chinese: From
Assimilation to Multiculturalism‖. Chinese Indonesians: State Policy,
Monoculture and Multiculture, 2004, h. 1-16.
245
Suryadinata, L. ―Kebijakan Negara Indonesia Terhadap Etnik Tionghoa: Dari
Asimilasi Ke Multikulturalisme ?‖. Antropologi Indonesia, no. 71, 2003, h. 1-
12.
Susanti, Lisa. ―Pengaruh Kolonial Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Cirebon
Tahun 1752-1830‖. Jurnal Prodi Ilmu Sejarah, vol. 3, no. 3, 2018, h. 274-288.
Susi, M., Purnama, D. A., Nany, I., Prima, A., & Krasnobaev, R. ―Cultural
Sciences‖. Cultural Sciences, vol. 34, no. 3, 2019.
Susilo, D., ―Chinese Cultural Values and its Influence on Chinese Indonesian
Entrepreneurial Culture‖. Asian People Journal (APJ), vol. 3, no. 1, 2020, h.
201-208.
Sutrisno, E. ―Confucius is Our Prophet: The Discourse of Prophecy and Religious
Agency in Indonesian Confucianism‖. Sojourn: Journal of Social Issues in
Southeast Asia, vol. 32, no. 3, 2017, h. 669-718.
Syarifah, M. ―Budaya dan Kearifan Dakwah‖. Jurnal al-Balagh, vol. 1, no. 1, 2016,
h. 23-24.
Tadjoeddin, M. Z. ―Inequality and Exclusion in Indonesia‖. Journal of Southeast
Asian Economies, vol. 36, no. 3, 2019, h. 284-303.
Tambrin, I. ―Batik Cirebon: Tinjauan Ornamen Batik Trusmi Cirebon‖, Jurnal Seni
Rupa dan Desain, vol. 2, no. 4. 2002, h. 1-13.
Taneo, M., Ndoen, F. A. & Neolaka, S. Y. ―History of Arrival and Development of
Chinese Ethnic in Kupang‖. International Journal of Multicultural and
Multireligious Understanding, vol. 6, no. 5, 2019, h. 356-369.
Tanggok, M. I. ―The Role of Chinese Communities lo the Spread of Islam in
Indonesia”. Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, vol. 7, no. 3, 2006, h.
249-262.
Tanomi, Erna dan Christiana, Elisa. ―Akulturasi Budaya Tionghoa dan Jawa dalam
Pertunjukan Liong Batik dan Wacinwa di Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta
tahun 2015‖. Century: Journal of Chinese Language, Literature and Cultur,
vol. 2, no. 1, 2014, h. 108-122.
Taqiyuddin, Muhammad. ―Panca Indera dalam Epistemologi Islam‖. Tasfiyah:
Jurnal Pemikiran Islam, vol. 4, no. 1, 2020, h. 113-138.
Tarde, G. & Baldwin, J. M. ―Imitation and Creativity‖. The Creativity Reader,
2019, h. 173.
Tendi, ―Surat Perjanjian 7 Januari 1681: Edisi Diplomatik Naskah‖. Jurnal
Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, vol. 8, no. 1, 2020, h. 39-
58.
Tendi, T., Marihandono, D. & Abdurakhman, A. ―Between the Influence of
Customary, Dutch, and Islamic Law: Jaksa Pepitu and Their Place in Cirebon
Sultanate History‖. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, vol. 57, no. 1, 2019,
h. 117-142.
Theo, R. & Leung, M. W. ―China‘s Confucius Institute in Indonesia: Mobility,
Frictions and Local Surprises‖. Sustainability, vol. 10, no. 2, 2018, h. 530.
Thurnwald, R. ―The Psychology of Acculturation‖. American Anthropologist, vol.
34, no. 4, 1932, h. 557-569.
Tingyu, Z. ―Ming shi (History of the Ming Dynasty)‖. Beijing: Zhonghua shuju,
vol. 285, no. 173, 1974.
246
Tjandrasasmita, Uka. ―Laksamana Cheng Ho dan Penyebaran Islam di Asia
Pasifik‖, Seminar Internasional Fakultas Dakwah IAIN Jakarta, 28 Agustus
1993.
Tolentino, R. P. G. ―Archaeology of Sacred Symbols: The Lost Meaning and
Interpretations‖. International Journal of Recent Innovations in Academic
Research, vol. 3, no. 10, 2019, h. 66-71.
Triggs, O. L. ―The Decay of Aboriginal Races (Illustrated)‖. The Open Court, no.
10, 1912.
Trimble, J. E. ―Introduction: Social change and acculturation‖. In Acculturation:
Advances in Theory, Measurement, and Applied Research, vol. 10, 2003, h. 3-
13.
Turner, S. & Allen, P. ―Chinese Indonesians in a rapidly changing nation: Pressures
of ethnicity and identity‖. Asia pacific viewpoint, vol. 48, no. 1, 2007, h. 112-
127.
Turner, V. ―Process, System, and Symbol: A New Anthropological
Synthesis‖. Daedalus, 1977, h. 61-80.
Turner, V. ―Symbolic Studies‖. Annual Review of Anthropology, vol. 4, 1, 1975, h.
145-161.
van den Berghe, P. L. ―Australia, Canada and the United States: Ethnic Melting
Pots or Plural Societies?‖. The Australian and New Zealand Journal of
Sociology, vol. 19, no. 2, 1983, h. 238-252.
Vuong, Q. H., Bui, Q. K., La, V. P., Vuong, T. T., Nguyen, V. H. T. & M. T. Ho,
―Cultural Additivity: Behavioural Insights from the Interaction of
Confucianism, Buddhism and Taoism in Folktales‖. Palgrave
Communications, vol. 4, no. 1, 2018, h. 1-15.
W, Rita Hadi. ―Pengaruh Intervensi Musik Gamelan Terhadap Depresi Pada Lansia
di Panti Wreda Harapan Ibu Semarang‖. Home, vol. 1, no. 2, 2013, h. 135-140.
Wah, S. S. ―Confucianism and Chinese Leadership‖. Chinese Management Studies,
vol. 4, no. 3, 2010, h. 280-285.
Wake, C. H. ―Raffles and the rajas: the founding of Singapore in Malayan and
British colonial history. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic
Society, vol. 48 (227), 1975, h. 47-73.
Waldmueller, J. M. ―Agriculture, Knowledge and the ‗Colonial Matrix of Power‘:
Approaching Sustainabilities from the Global South‖. Journal of Global
Ethics, vol. 11, no. 3, 2015, h. 294-302.
Wang, R. ―Inheritance of Intangible Cultural Heritage of Oroqen Ethnic Group
Based on Computer Network Culture‖. In Journal of Physics: Conference
Series, vol. 1574, no. 1, (IOP Publishing, 2020), h. 012003.
Wang, S. Y., Wong, Y. J. & Yeh, K. H. ―Relationship Harmony, Dialectical
Coping, and Nonattachment: Chinese Indigenous Well-being and Mental
Health‖. The Counseling Psychologist, vol. 44, no. 1, 2016, h. 78-108.
Wasino, W., Putro, S., Aji, A., Kurniawan, E. & Shintasiwi, F. A. ―From
Assimilation to Pluralism and Multiculturalism Policy: State Policy Towards
Ethnic Chinese in Indonesia‖. Paramita: Historical Studies Journal, vol. 29,
no. 2, 2019, h. 213-223.
247
Wei, C., Dai, S., Xu, H. & Wang, H. ―Cultural worldview and cultural experience in
natural tourism sites. Journal of Hospitality and Tourism Management, vol. 43,
2020, h. 241-249.
al Wekhian, J. ―Acculturation Process of Arab-Muslim Immigrants in the United
States‖. Asian Culture and History, vol. 8, no. 1, 2016, h. 89-99.
Wibowo, P. ―Tionghoa dalam Keberagaman Indonesia: Sebuah Perspektif Historis
tentang Posisi dan Identitas‖. In Proceeding of The 4th International
Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity, and Future”, vol. 13,
2012.
Wibowo, Priyanto. ―The 1740 Racial Tragedy and loss off Batavia Sugarcane
Industries‖. Paramita, vol. 23, no. 2, 2013, h. 127-136.
Widiaty, I., Riza, L. S. & Abdullah, A. G. ―A Preliminary Study on Augmented
Reality for Learning Local Wisdom of Indonesian Batik in Cocational
Schools‖. In 2015 International Conference on Innovation in Engineering and
Vocational Education, (Atlantis Press, 2015).
Widodo, J. ―Admiral Zheng He and pre-Colonial Coastal Urban Development in
Southeast Asia‖. Inaugural Lecture organized by Friends of Zheng He Society,
(Singapore: Unpublis, 2003).
Widyanti, A., Susanti, L., Sutalaksana, I. Z. & Muslim, K. ―Ethnic differences in
Indonesian Anthropometry Data: Evidence from Three Different Largest
Ethnics‖. International Journal of Industrial Ergonomics, vol. 47, 2015, h. 72-
78.
Widyonugrahanto, W., Lubis, N. H., Mahzuni, D., Sofianto, K., Mulyadi, R. M. &
Darsa, U. A. ―The Politics of the Sundanese Kingdom Administration in
Kawali-Galuh‖. Paramita: Historical Studies Journal, vol. 27, no. 1, 2017, h.
028-033.
Wijayanto, E. & Soekarba, S. R. ―The Cultural Evolution of Local Islamic Values
on the Muludan Tradition in Cirebon: A Memetics Perspective‖. International
Review of Humanities Studies, vol. 4, no. 2, 2019.
Wildan, D. Sunan Gunung Jati: Pembumian Islam dengan Pendekatan Struktural
dan Kultural (Antara Fiksi dan Fakta), (Bandung, Humaniora Utama Press,
2002), h. 272-273.
Wilson, T. A. ―Culture, Society, Politics, and the Cult of Confucius‖. On Sacred
Grounds: Culture, Society, Politics, and the Formation of the Cult of
Confucius, 2020, h. 7.
Wiyoso, J. ―Pengaruh Difusi dalam Bidang Musik Terhadap Karawitan, Harmonia‖.
Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni, vol. 3, no. 2, 2002.
Woo, B. D., Maglalang, D., Ko, S., Park, M., Choi, Y. & Takeuchi, D. T. ―Racial
discrimination, ethnic-racial socialization, and cultural identities among Asian
American youths‖. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 2020.
Xie, Y. & Greenman, E. ―The social context of assimilation: Testing implications of
segmented assimilation theory‖. Social Science Research, vol, 40, no. 3, 2011,
h. 965-984.
Xing, G. ―Conflict and Harmony between Buddhism and Chinese
Culture‖. International Journal of Buddhist Thought and Culture, vol. 25,
2015, h. 83-105.
248
Xing, L., Zhang, J., Klein, H., Mayor, A., Chen, Y., Dai, H.... & Dong, S. ―Dinosaur
Tracks, Myths and Buildings: The Jin Ji (Golden Chicken) Stones from Zizhou
Area, Northern Shaanxi, China‖. Ichnos, vol. 22, no. 3-4, 2015, h. 227-234.
Xinyu, Y. & Al-Muhsin, M. A. ―Comparative Study on Myth Between Chinese and
Arabic: Phoenix as An Example‖. International Journal of Humanities,
Philosophy and Language, vol. 3, no. 10, 2020, h. 12-17.
Yakin, H. S. M. & Totu, A. ―The Semiotic Perspectives of Peirce and Saussure: A
Brief Comparative Study‖. Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 155,
2014, h. 4-8.
Yang, F. ―Taoist wisdom on individualized teaching and learning—Reinterpretation
through the perspective of Tao Te Ching‖. Educational Philosophy and
Theory, vol. 51, no. 1, 2019, h. 117-127.
Yani, A. ―Pengaruh Islam Terhadap Makna Simbolik Budaya Keraton-Keraton
Cirebon. Holistik, vol. 12, no. 1, 2011, h. 181-196.
Yildirim, C. & Correia, A. P. ―Exploring the dimensions of nomophobia:
Development and validation of a self-reported questionnaire‖. Computers in
Human Behavior, vol. 49, 2015, h. 130-137.
Yildiz, E. P., Çengel, M. & Alkan, A. ―Investigation of Nomophobia Levels of
Vocational School Students According to Demographic Characteristics and
Intelligent Phone Use Habits‖. Higher Education Studies, vol. 10, no. 1, 2020,
h. 132-143.
Yinger, J. M. ―Toward a Theory of Assimilation and Dissimilation‖. Ethnic and
Racial Studies, vol. 4, no. 3, 1981, h. 249-264.
Yu, D. S. & Malik, K. M. A. ―Cultural Islam in Northern Europe‖. Baltic
Region, vol. 11, no. 3, 2019.
Yuhan, X. I. E. & Chen, G. E. ―Confucius‘ Thoughts on Moral Education in
China‖. Cross-Cultural Communication, vol. 9, no. 4, 2013, h. 45-49.
Yulianto, Rahmad. ―Tasawuf Transformatif sebagai Solusi Problematika Manusia
Modern dalam Perspektif Pemikiran Tasawuf Muhammad Zuhri‖. Teosofi, vol.
4, no. 1, 2014, h. 56-87.
Yusli, Utami Dwi dan Rachma, Nurullya. ―Pengaruh Pemberian Terapi Musik
Gamelan Jawa Terhadap Tingkat Kecemasan Lansia‖. Jurnal Perawat
Indonesia, vol. 3, no 1, 2019, h. 72-78.
Yusuf, M. ―When Culture Meets Religion: The Muludan Tradition in the Kanoman
Sultanate, Cirebon, West Java‖. Al Albab-Borneo Journal of Religious Studies
(BJRS), vol. 2, no. 1, 2013.
Yusuf, S. A. ―Aspects of Architecture Infrastructures Acculturation Function, form
and the Meaning of the Christian Church building Pniel Blimbingsari in
Bali. Arteks: Jurnal Teknik Arsitektur, vol. 1, no. 1, 2016, h. 15-30.
Zarifa, A. P. ―Masjid dan Makam Sendang Duwur: Perwujudan Akulturasi‖. In
Prosiding Seminar Heritage IPLBI, 2017, h. 381-384.
Zayyad, S. B. & Sinclair, B. R. ―Culture, Context+ Environmental Design:
Reconsidering Vernacular in Modern Islamic Urbanism‖. Architectural
Research: Addressing Societal Challenges, vol. 1, 2017, h. 535-542.
Zeman, J. ―Peirce‘s Theory of Signs‖. A Perfusion of Signs, 1977, h. 22-39.
249
Zhang, D. ―Cultural Symbols in Chinese Architecture‖. Architecture and Design
Review, vol. 1, 2018, h. 1-19.
Zhao, B. ―Chinese-style ceramics in East Africa from the 9th to 16th century: A
case of changing value and symbols in the multi-partner global
trade‖. Afriques. Débats, Méthodes et Terrains D‟histoire, no. 06, 2015.
Zhuang, W. ―Photography and Chineseness: Reflections on Chinese Muslims in
Indonesia‖. Inter-Asia Cultural Studies, vol. 20, no. 1, 2019, h. 107-130.
Zuhdi, Muhammad Harfin. ―Istiqomah dan Konsep Diri Seorang Muslim‖. Religia,
vol. 14, no. 1, 2011, h. 111-128.
Zuhdi, Muhammad Harfin. ―Konsep Kepemimpinan dalam Islam‖. Akademika, vol.
19, no. 1, 2014, h. 35-57.
―Java, Boordevol Cultuur‖, dalam Algemeen Dagblad, Rotterdam, 18-05-1993, h.
25.
―Sultanskoets nooit meer als nieuw‖, Nieuwsblad van het Noorden, Groningen, 29-
12-1993, h. 3.
Tesis dan Disertasi
Bukhari, Zaenuddin. Mistisisme Jawa: Studi Serat Sastra Gendhing Sultan Agung,
(Disertasi IAIN Walisongo, 2012).
Chiou, S. Y. Search of New Social and Spiritual Space: Heritage, Conversion, and
Identity of Chinese-Indonesian Muslims, (Doctoral Dissertation, Utrecht
University, 2012).
Hew, W. W. Negotiating Ethnicity and Religiosity: Chinese Muslim Identities in
Post-new Order Indonesia, (A thesis submitted for the degree of Doctor of
Philosophy Department of Political and Social Change School of International,
Political and Strategic Studies College of Asia and the Pacific of The
Australian National University, 2011).
Muhaimin, A. G. The Islamic Traditions of Cirebon: Ibadat and Adat Among
Javanese Muslims, (Unpublished PhD Thesis, The Australian National
University, Canberra, 1995).
Siddique, S. Relics of the Past: A Sociological Study of the Sultanates of Cirebon,
West Java, (Ph.D. Dissertation, Bielefeld, 1977).
Sunanto, Musyrifah. Syarif Hidayatullah Seorang Wali Penyebar Islam di Jawa
Barat, (Disertasi PPS. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999).
Tjiptoatmojo, F. A S. Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura Abad XIX sampai
Medio Abad XIX, (Disertasi Doktoral Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM
Yogyakarta, 1983).
Triawan, D. W. Analisis Motif Ragam Hias pada Alat Transportasi Tradisional
Keraton Cirebon, (Tesis S2 Program Studi Pendidikan Seni, Sekolah
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2017).
Wawancara Pribadi
Wawancara dengan Ajat (Budayawan dan Pemandu Taman Air Sunyaragi) pada
tanggal 16 Juli 2020.
250
Wawancara dengan Bambang Irianto (Budayawan Cirebon) pada tanggal 08 Juli
2020.
Wawancara dengan Hafidz (Budayawan dan Pemandu Keraton Kasepuhan Cirebon)
pada tanggal 17 Juli 2020.
Wawancara dengan Iman Sugiman (Pemandu Keraton Kasepuhan Cirebon) pada
tanggal 09 Juli 2020.
Wawancara dengan Opan Safari (Filolog dan Budayawan Cirebon) pada tanggal 19
Juli 2020.
Wawancara dengan Permadi (Tokoh Mayarakat Tionghoa) pada tanggal 26
September 2019
Sumber Internet
―Hadiah Terbesar Bangsa Cina ke Indonesia adalah Agama Islam‖. Diambil dari:
https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islamnusantara/13/09/27/mtrx43-
habibie-hadiah-terbesar-bangsa-cina-ke-indonesia-adalah-islam. (Diakses pada
17 Agustus, 2020).
Ernawati, Jujuk & Permatasari, Adinda. ―Sejarah Piring Selampad, Motif Batik
Langka dari Cirebon‖. Diambil dari: https://www.viva.co.id/gaya-
hidup/gaya/886954-sejarah-piring-selampad-motif-batik-langka-dari-cirebon.
(Diakses pada 24 Februari, 2017).
Diambil dari: https://www.radarcirebon.com/2018/03/23/cirebon-tionghoa-
perkawinan-budaya-yang-melekat/ . (Diakses pada 30 November, 2020).
Diambil dari: http://www.nabilfoundation.org/artikel/9/istilah-cina-china-dan-
tionghoa . (Diakses pada 30 November, 2020).
Radar Cirebon, ―Sejarah Warga Tionghoa di Cirebon‖. Diambil dari:
http://www.radarcirebon.com/tag/sejarah-warga-tionghoa (Diakses pada 23
Januari, 2019).
249
GLOSARIUM
Adat : Gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-
nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan
dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu
kelompok masyarakat.
Kristen : Kristen adalah agama Abrahamik monoteistik
berasaskan riwayat hidup dan ajaran Yesus
Kristus, yang merupakan inti sari agama.
Akulturasi : Akulturasi adalah suatu proses sosial yang
timbul manakala suatu kelompok manusia
dengan kebudayaan tertentu dihadapkan
dengan unsur dari suatu kebudayaan asing.
Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan
diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa
menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan
kelompok itu sendiri.
Asimilasi : Asimilasi adalah pembauran satu kebudayaan
yang disertai dengan hilangnya ciri khas
kebudayaan asli sehingga membentuk
kebudayaan baru.
Budaya : Budaya adalah suatu gaya hidup yang
berkembang dalam suatu kelompok atau
masyarakat dan diwariskan secara turun
menurun dari generasi ke generasi.
Buddhisme : Buddhisme adalah ajaran agama yang
mengajarkan agar menjunjung tinggi dan
menghargai hak asasi wanita sekaligus
menghilangkan kasta-kasta. Di samping itu,
ajaran ini juga sangat menjunjung tinggi nilai-
nilai demokrasi.
Chauvinisme : Chauvinisme adalah sikap cinta tanah air yang
berlebihan sehingga menganggap bangsannya
adalah bangsa terbaik dan menganggap bangsa
lain rendah.
Cina Peranakan : Cina Peranakan adalah istilah yang digunakan
oleh para keturunan imigran Tionghoa yang
sejak akhir abad ke-15 dan abad ke-16 telah
berdomisili di kepulauan Nusantara (sekarang
Indonesia), termasuk Malaya Britania
(sekarang Malaysia Barat dan Singapura). Di
beberapa wilayah di Nusantara sebutan lain
juga digunakan untuk menyebut orang
Tionghoa Peranakan, seperti “Tionghoa
Benteng” (khusus Tionghoa-Manchu di
Tangerang) dan “Kiau-Seng” (di era kolonial
Hindia Belanda).
Difusi : Difusi adalah suatu proses penyebaran unsur-
unsur kebudayaan ke seluruh dunia. Salah satu
250
bentuk difusi adalah penyebaran unsur-unsur
kebudayaan yang terjadi karena dibawa oleh
kelompok-kelompok manusia yang bermigrasi
dari satu tempat ke tempat lain di dunia.
Ekspansi : Aktivitas memperbesar atau memperluas usaha
yang ditandai dengan penciptaan pasar baru,
perluasan fasilitas dan sebagainya.
Eksploitasi : Politik pemanfaatan yang dilakukan sewenang-
wenang (berlebihan) terhadap subyek
eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi
semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa
kepatutan, keadilan dan kompensasi
kesejahteraan.
Fasisme : Fasisme adalah paham yang berdasarkan
prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang
mutlak/absolut di mana perintah pemimpin dan
kepatuhan berlaku tanpa pengecualian.
Menjadi sangat penting dalam ideologi fasis,
karena ideologi ini selalu membayangkan
adanya musuh, sehingga pemimpin dan militer
harus kuat menjaga negara.
Gemeente : Kota Praja
Imigrasi : Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu
negara-bangsa (nation-state) ke negara lain, di
mana ia bukan merupakan warga negara.
Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk
menetap permanen yang dilakukan oleh
imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk
jangka waktu pendek tidak dianggap imigran.
Irigasi : Usaha penyediaan dan pengaturan air untuk
menunjang pertanian yang meliputi irigasi air
permukaan, air bawah tanah, pompa dan rawa
Islamis : Orang yang memiliki ideologi atau keyakinan
bahwa Islam adalah pedoman bagi segala segi
kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi,
politik, budaya, serta kehidupan pribadi.
Islamisasi : Proses konversi masyarakat menjadi Islam
Komunisme : Komunisme adalah ideologi yang berkenaan
dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi
yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat
komunis dengan aturan sosial ekonomi
berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi
dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan
negara.
Konfusianisme : Konfusianisme adalah inti ajaran filsafat Cina
yang mengajarkan peningkatan moral dan etika
manusia.
Masyarakat Pribumi : Orang/penduduk asli.
Monopoli : Suatu kondisi bisnis di mana ada satu
251
perusahaan yang memiliki layanan yang
dibutuhkan oleh banyak orang.
Mauludan : Muludan adalah salah tradisi masyarakat
Muslim-Sunda terkait dengan hari kelahiran
Nabi Muhammad saw. Sebagian orang Sunda
Muslim menyebutnya Muludan atau Maulidan
merujuk pada Maulid (hari kelahiran) Nabi
Muhammad saw. Kelahiran Muhammad saw.
sediri diyakini tepat pada tanggal 12 Rabi’ul
Awal pada kalender Hijriyah. Namun orang
Sunda-Muslim menyebut bulan ini dengan
sebutan bulan Mulud, karena terkait dengan
kelahiran Nabi.
Nasionalisme : Paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan
negaranya sendiri.
Nativisme : Nativisme adalah pandangan bahwa
keterampilan-keterampilan atau kemampuan-
kemampuan tertentu bersifat alamiah atau
sudah tertanam dalam otak sejak lahir.
Panjang Jimat Panjang Jimat adalah tradisi Maulid Nabi di
Cirebon. Sebagai peringatan hari kelahiran
Nabi Muhammad SAW atau maulid Nabi
kerap di istimewakan. Tujuannya, tidak lain
untuk mengenang dan selalu meneladani nabi
Muhammad SAW.
Pedukuhan : Desa
Rajaban : Rajaban adalah sebutan bagi perayaan hari
Isra' Mi'raj bagi umat Islam yang jatuh pada
bulan Rajab.
Ruwahan : Ruwahan merupakan tradisi kebudayaan Jawa
untuk mendoakan orang yang telah meninggal
dunia, seperti oran tua, kakek, nenek, tokoh
pendiri kampung, wali, dan lainnya.
Saparan : Saparan adalah tradisi Jawa yang dilaksanakan
saat bulan Safar pada kalender Jawa.
Segregasi : Pemisahan kelompok ras atau etnis secara
paksa; Bentuk pelembagaan diskriminasi yang
diterapkan dalam struktur sosial.
Slametan : Selametan adalah sebuah tradisi ritual yang
dilakukan oleh masyarakat Jawa. Selametan
juga dilakukan oleh masyarakat Sunda dan
Madura. Selametan adalah suatu bentuk acara
syukuran dengan mengundang beberapa
kerabat atau tetangga. Secara tradisional acara
syukuran dimulai dengan doa bersama, dengan
duduk bersila di atas tikar, melingkari nasi
tumpeng dengan lauk pauk.
Suroan : Suroan adalah tradisi yang turun temurun yang
masih dilakukan oleh masyarakat jawa sampai
252
sekarang. suroan dilakukan setiap tanggal satu
Suro atau tanggal satu muharam. Tradisi
malam satu Suro menitikberatkan pada
ketentraman batin dan keselamatan.
Karenanya, pada malam satu Suro biasanya
selalu diselingi dengan ritual pembacaan doa
dari semua umat yang hadir merayakannya.
Hal ini bertujuan untuk mendapatkan berkah
dan menangkal datangnya marabahaya.
Syawalan : Syawalan merupakan tradisi di kalangan
masyarakat Jawa setelah berlebaran (hari raya
Idul Fitri).
Taoisme : Taoisme adalah ajaran yang menganjurkan
hidup dalam harmoni dengan tao/dao (alam
semesta).
Vasal : Vasal adalah seseorang yang menjalin
hubungan dengan monarki yang berkuasa—
biasanya dalam bentuk dukungan militer,
perlindungan bersama (mutual protection), atau
pemberian upeti, dan menerima jaminan dan
imbalan tertentu sebagai gantinya.
253
INDEKS
A
Asia Tenggara : 1, 3, 4, 7, 58, 64, 105,
106, 124, 142, 143
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) : 10,
11, 123
Arab : 3, 8, 23, 25, 55, 57, 63, 64, 65,
69, 75, 87, 89, 92, 103, 104, 105,
123, 125, 129, 133, 142, 165, 173,
185, 188, 189
B
Batavia : 57, 81, 91, 109, 135, 190, 207
Belanda : 6, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 22,
23, 25, 26, 30, 45, 55, 58, 61, 63,
64, 65, 66, 85, 86, 87, 90, 91, 109,
122, 129, 134, 141, 144, 207, 208
BJ. Habibi : 123
C
Che Li Wen : 12
Cheng Ho : 4, 5, 6, 11, 12, 19, 24, 30,
55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64,
94, 95, 104, 105, 106, 107, 108,
116, 125, 126, 133, 150, 170, 207
Ciamis : 81, 86, 108, 133
Cirebon : 5, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
30, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 104, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115,116, 125, 127, 128, 129,
131, 132, 133, 134, 135, 137, 138,
139, 144, 145, 147, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 156, 157, 163, 165,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 177, 179, 181, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 192, 193,
94, 196, 197, 198, 199, 201, 203,
204, 207, 208, 209, 210
D
Diego Ribeiro : 12
Dinasti Chou : 2
Dinasti Ming : 4, 5, 13, 105, 133, 169
Dinasti Tang : 3
E
Eropa : 2, 6, 7, 25, 40, 43, 55, 65, 89,
113, 114, 135, 142, 165, 185, 188,
190
F
Fa Hian : 2
G
Garut : 60, 99, 107, 108, 133, 185, 188
Gujarat : 55, 73,76, 132, 141
I
Islamisasi : 21, 55, 58, 61, 68, 97, 98,
100, 101
I-Tsing : 2
India : 2, 7, 8, 40, 42, 43, 53, 55, 57,
65, 69, 89, 119, 172, 173, 174, 185,
189
Islam : 1, 5, 6, 7, 11, 13, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 41,
42, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76,
78, 79, 80, 81, 87, 88, 89, 92, 93,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104,
105, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 115, 117, 125, 128, 129, 131,
132, 133, 134, 136, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 151,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 160,
161, 164, 165, 168, 173, 175, 178,
179, 181, 183, 192, 193, 194, 195,
199, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 209
J
Jakarta : 49, 58, 63, 64, 65, 125
Jawa Timur : 3, 56, 58, 94, 98, 112,
145
254
Jawa Tengah : 24, 59, 63, 66, 86, 89,
112, 129
J. H. J. Sigal : 90
Jawa Barat : 3, 24, 58, 68, 73, 84, 89,
90, 92, 98, 99, 100, 125, 132, 184,
185, 188, 209, 210
Jawa : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 17, 18, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 30, 41, 48, 55,
56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 69, 74, 75, 76, 77, 81, 87, 88,
89, 91, 95, 96, 99, 104, 105, 106,
107, 125, 128, 129, 140, 146, 154,
156, 165, 177, 188, 193, 194, 195,
197, 198, 202
K
Kaisar Mongol : 4
Kaisar Tiongkok : 3, 6, 13, 143, 148,
196, 207
Kaisar Wan Ming : 2
Kaisar Yung-Le : 4
Kalimantan : 2, 7, 105
Kediri : 3, 4, 82
Ken Arok : 4
Kerajaan Borneo : 3
Kerajaan Panjalu : 3, 4
Kerajaan Tarumanegara : 3
Keraton Kacirebonan : 90, 139, 156
Keraton Kanoman : 90, 156, 173
Keraton Kasepuhan : 19, 20, 24, 25, 27,
30, 83, 90, 135, 137, 138, 139,
140,141, 142, 143, 144, 145, 147,
149, 151, 153, 154, 155, 156, 157,
165, 168, 170, 171, 177, 182, 196,
206, 209
Keraton Keprabonan : 90
Keresidenan Cirebon : 86
Kertanegara : 4
Konfusianisme : 7, 116, 117, 119, 208
Kubilai Khan : 4
Kuningan : 71, 81, 86, 98, 99, 100, 102,
133, 185, 201
L
Lie Guan Cang : 13, 207
Lie Guan Hian : 13, 207
M
Ma Huan : 5, 12, 56, 57, 58, 60, 61,
106, 134
Majalengka : 81, 86, 99
Majapahit : 4, 58, 60, 61, 78, 102, 134,
140, 145
Makam Astana Gunung Jati : 19, 26,
137, 165, 170
Malaka : 57, 89, 95, 96
Mekah : 74, 75
N
Nabi Muhmamad SAW : 75, 97, 102,
152, 154, 155, 157, 164, 169, 175,
179
Nusantara : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19,
20, 21, 25, 30, 31, 55, 63, 64, 68,
81, 87, 89, 90, 96, 97, 98, 100, 101,
104, 105, 106, 122, 125, 126, 127,
131, 132, 146, 199
O
Ong Tien Nio : 13, 19, 61, 78, 108,
109, 133, 134, 135, 147, 150, 169,
170, 174, 177, 190, 201, 207
Orde Baru : 8, 9, 10, 17, 18, 45, 67,
118, 122
P
Palembang : 57, 60, 94
Pate Quedir : 13, 89, 94
Persatuan Islam Tionghoa Indonesia
(PITI) : 11
Persia : 55, 57, 69, 75, 92, 125, 142,
185, 189
Politik Etis : 90
R
Raja Singosari : 4
S
Samudera Pasai : 5
Sarekat Islam (SI) : 66
255
Soeharto : 10, 123
Sriwijaya : 2, 3, 57
Sumanto Al Qurtuby : 4, 24, 26, 55, 56,
58, 59, 63, 64, 125
Sumatera : 7, 58, 62, 69, 101
Sunan Gunung Jati : 13, 19, 59, 60, 61,
68, 72, 76, 77, 78, 79, 89, 90, 94,
98, 99, 100, 101, 102, 107, 108,
109, 112, 128, 130, 131, 133, 134,
135, 139, 145, 153, 154, 157, 166,
168, 169, 172, 189, 190, 193, 201,
207
Surabaya : 5, 56, 57, 58, 69, 88, 92,
104, 106, 125
Susilo Bambang Yudhoyono : 10
Syarif Hidayatullah : 13, 72, 75, 76, 77,
78, 80, 101, 149, 151, 153, 156,
191, 201
T
Tiongkok : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13,
14, 17, 19, 22, 23, 35, 26, 57, 59,
60, 61, 63, 64, 69, 73, 89, 92, 95,
96, 105, 106, 108, 117, 118, 119,
120, 121, 123, 124, 126, 129, 133,
134, 135, 136, 141, 142, 143, 144,
147, 148, 165, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 176, 177, 181, 182, 183,
185, 188, 189, 190, 195, 196, 198,
201, 203, 206, 207
Tan Eng Hoat : 60, 107, 108, 133, 207
Taoisme : 7, 24, 116, 117, 119, 136,
208
Tome Pires : 6, 12, 58, 87, 89, 91, 92,
93, 94, 95, 96
V
Vereenigde Oost-Indische Compagnie
(VOC) : 113, 58, 81, 82, 83, 84, 85,
95, 109, 113, 114, 115, 135, 207
Z
Zainal Abidin Bahian Syah : 5