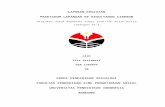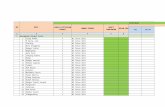BAB 1 KOSTRUKSI NEGARA KESULTANAN SERDANG, 1723-1946
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of BAB 1 KOSTRUKSI NEGARA KESULTANAN SERDANG, 1723-1946
1
BAB SATU
PROLOG
1. Latar Belakang Masalah MASA TAHUN 1946 merupakan suatu masa yang cukup kritis dalam awal Pemerintahan Republik,
Mr.T.M. Hasan, Gubernur Sumatera, mencoba menampung aspirasi kaum bangsawan melalui
kebijaksanaan rekonsialisainya. Sangat dipenulisngkan, kebijakan Pemerintah Republik ternyata tidak
berhasil. Para pendukung Republik yang menganut garis keras mengambil jalan pintas untuk
mengenyahkan golongan bangsawan dengan sistem feodalnya melalui revoluasi sosial pada bulan Maret
1946.
Revolusi sosial ternyata susah dikendalikan dan menyambar siapa saja yang dipandang berbau feodal
dan kolonial, termasuk birokrat-birokrat Republik yang hanya memakai “dasa”. Revolusi sosial telah
memakan korban berpuluh-puluh aristokrasi Negara KeSultanan Serdang, tetapi semangat untuk tetap
menjadi nomor satu di “rumahnya sendiri” tidak pernah surut dari mereka. Lebih jauh revolusi sosial
telah membuat Republik mendapat nama buruk dari peristiwa tersebut.
Konflik kelas dan etnis merupakan unsur penting dalam proses dekolonisasi di Negara KeSultanan
Serdang . Konflik itu tetap menjadi kekuatan destabilisasi hingga periode pasca kolonial. Konflik antar
penduduk asli dengan kaum pendatang, antara orang Melayu dengan non Melayu, telah menjadi ciri-ciri
khusus yang mewarnai peristiwa politik internal di wilayah Negara KeSultanan Serdang . Konflik itu
juga telah mewarnai hubungan politik antara Jakarta dan Negara KeSultanan Serdang.1
2. Batasan Masalah Buku ini akan merekontruksikan peristiwa-peristiwa seputar runtuhnya Negara KeSultanan Serdang.
Pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab adalah : pertama, faktor-faktor apa yang melatarbelakangi
munculnya Negara KeSultanan Serdang. Kedua, bagaimanakah proses pelepasan diri dari KeSultanan
Deli, hingga menjadi negara Negara KeSultanan Serdang. Ketiga, faktor-faktor apa yang mempercepat
dan menghambat runtuhnya Negara KeSultanan Serdang.
Pada dasarnya kausalitas peristiwa sejarah tidaklah memiliki suatu batasan yang mutlak, baik dari
aspek periodisasi maupun cakupan masyarakat yang diakibatkannya, namun demikian agar suatu studi
sejarah dapat dilaksanakan secara lebih mendalam, perlu dibuat batasan-batasan khusus. Dengan
demikian dapat ditelusuri langkah-langkah reconaissance (identifikasi masalah) dan feasibility
(kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan dalam penelitian).2
Ruang lingkup geografi sebagai unit analisis buku ini adalah Negara KeSultanan Serdang.3 Meskipun
demikian buku ini akan memperhatikan aspek-aspek supra lokal. Potret sejarah lokal Sumatera Utara
justru menjadi bagian yang sangat mempengaruhi potret sejarah nasional. Dalam buku ini akan tampak
1Herberth Feith. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. (New York : Cornell University
Press, 1962), hlm. 393-396) 2Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Histografi Indonesia Suatu Alternatif. (Jakarta;
Gramedia, 1982), hlm. 89. 3Kesultanan Serdang yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah daerah bekas Kabupaten Deliserdang, yang
sekarang menjadi bagian Kabupaten Serdang Bedagai.
2
jelas bahwa terjadi saling pengaruh yang sangat kuat antara peristiwa-peristiwa lokal dan nasional dalam
konteks sejarah Negara KeSultanan Serdang.
Unit analisis studi ini adalah pertumbuhan negara, tetapi mengingat luasnya problematika di seputar
Ketatanegaraan Melayu di Negara KeSultanan Serdang , maka sasaran buku ini akan dibatasi pada
Sumber Hukum Material Daulat–Durhaka, Sistem Demokrasi atau Kedaulatan KeSultanan, Asas
Pembagian Kekuasaan, Hakikat Pemisahan Diri dari KeSultanan Deli, Sejarah Perkembangan
Ketatanegaraan KeSultanan, Bentuk dan Sistem Pemerintahan, Struktur, Sistem dan Susunan
Kelembagaan Negara dalam memperjuangkan, mengembangkan dan mempertahankan Negara
KeSultanan Serdang.
3. Tujuan Penulisan Buku ini memiliki konsekuensi mendebukukan lembaga-lembaga kekuasaan, sumber ekonomi, kultur
dan saluran yang dipakai oleh tokoh-tokoh elite Negara KeSultanan Serdang. Secara tematis buku ini
termasuk studi sejarah politik, maka di dalamnya akan dijelaskan pola-pola distribusi kekuasaan yang
terkait dengan struktur sosial pada masa itu. Pola distribusi kekuasaan merupakan proses politik yang
didalamnya menyangkut kompleksitas hubungan : pemimpin dan pengikut, kekuasaan dan ideologi,
ideologi dan mobilisasi, solidaritas dan loyalitas.4
Rentang waktu yang ditelusuri selama dua ratus delapan belas tahun yakni dari tahun 1728 sampai
tahun 1946. Tahun 1728 diambil sebagai awal studi karena pada tahun inilah Negara KeSultanan
Serdang didirikan di Rantau Panjang. Meskipun demikian akan dibicarakan juga peristiwa-peristiwa
yang terjadi sebelum tahun 1728, yakni merentang sampai tahun 1720. Ini dimaksudkan untuk
menekankan pentingnya kesinambungan sejarah dalam menerangkan munculnya ide-ide pendirian
Negara KeSultanan Serdang.
Perhatian khusus diberikan pada dekade 1946-an sebagai proses runtuhnya Negara KeSultanan
Serdang. Proses itu terjadi dalam bingkai transformasi struktur masyarakat yang masih bersifat feodal
dan kesukuan ke struktur masyarakat demokratis. Dengan kata lain, proses keruntuhan Negara
KeSultanan Serdang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peristiwa Revoluasi Nasional.
4. Kerangka Konseptual dan Pendekatan Untuk menganalisis dinamika Negara KeSultanan Serdang sebagai proses politik, yang berkaitan
dengan pola-pola susunan dan bentuk negara; sumber ketatanegaraan, azas ketatanegaraan, sejarah
ketatanegaraan, bentuk dan sistem pemerintahan; tugas-tugas dan hubungan antar kelembagaan negara
perlu dipergunakan pendekatan dan konsep-konsep ilmu tata negara,5 di luar disiplin sejarah.
Peminjaman konsep-konsep ini diharapkan dapat memperjelas fenomena sejarah yang akan
didebukukan. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pendekatan sosio-legal. Melalui pendekatan ini
Negara KeSultanan Serdang akan dipandang sebagai negara yang berdaulat.
Agar pembahasan tidak keluar dari sasaran, maka perlu disepakati beberapa kerangka konseptual.
Konsep negara berangkali perlu mendapat penegasan lebih lanjut. Menurut Soenarko,6 negara adalah
organisasi sosial yang memiliki daerah, warga negara, dan kekuasaan, sedangkan Patrick Dunleavy dan
Bremdan O’Leary memandang negara sebagai lembaga sosial yang yang bertugas menjaga keteraturan
sosial atau stabilitas sosial. Secara organisatoris negara adalah suatu tipe pemerintahan yang ditandai
dengan lima kriteria. Pertama, negara secara jelas memisahkan lembaga atau seperangkat lembaga, juga
dibedakan dari masyarakat lainnya dalam hal menciptakan identifikasi publik dan lingkungan pribadi.
4Sartono Kartodirdjo. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah (Jakarta : Gramedia, 1992), hlm.
46-47. 5Ibid, hlm.120-123 6Soenarko, Susunan Negara Kita Sejak Penyerahan Kedaulatan, (Jakarta : Djambatan, 1951), hlm. 10-13.
3
Kedua, negara adalah penguasa atau kekuasaan tertinggi di wilayahnya, dan hukum publik dibentuk oleh
pejabat negara dan didukung oleh monopoli kekuasaan formal. Ketiga, kedaulatan negara diperluas di
atas semua individu dalam wilayah kekuasaan negara, dan ditetapkan secara sama juga bagi mereka yang
menduduki jabatan formal di pemerintah. Keempat, pegawai negara kebanyakan direkrut dan dilatih
untuk membentuk suatu gaya birokratis. Kelima, negara memiliki kemampuan untuk mengumpulkan
dana dalam rangka membiayai aktivitas negara untuk kepentingan rakyat.7
Jhon Schwarzmantel menyatakan, bahwa negara adalah asosiasi politik utama (central political
association). Negara baik yang kuno maupun modern adalah alat kekuasaan dan alat pemaksa. Aspek
pemaksa yang menjadi ciri utama satu negara ditunjukkan dengan adanya kontrol negara terhadap semua
warga yang secara tipikal melibatkan pemaksaan (coercion). Negara modern muncul sebagai alat
kekuasaan khusus, dan terpisah dari kelompok tertentu yang secara kebetulan menguasai negara pada
saat tertentu. Oleh karena itu negara adalah seperangkat iNegara KeSultanan Serdang itusi yang
merupakan alat kekuasaan khusus.8
Dalam mempelajari sejarah suatu negara, penting sekali untuk dianalisis hubungan antara negara dan
masyarakat. Suatu negara eksis karena adanya hubungan dengan masyarakat. Pieere Rosanvallon
sebagaimana dikutip oleh Schwarzmantal menyebutkan, bahwa ada empat aspek hubungan negara-
masyarakat sipil (civil society). Pertama, menurut idel demokrasi, negara dibentuk sebagai suatu negara
bangsa berfungsi sebagai suatu iNegara KeSultanan Serdang rumen pemersatu. Negara membentuk
bangsa, menciptakan, memperkuat ikatan sosial. Ketiga, negara sebagai welfare state adalah alat untuk
memenuhi kebutuhan rakyat. Keempat, negara sebagai pengatur ekonomi dan pengendali ekonomi. Hal
ini adalah suatu tugas yang mengharuskan adanya campur tangan dalam ekonomi untuk menjamin
tersedianya barang-barang, seperti lapangan kerja yang cukup, stabilitas moneter, dan pertumbuhan
ekonomi.9
Untuk memahami dengan jelas bagaimana sebenarnya bentuk negara Negara KeSultanan Serdang,
perlu dipergunakan perpaduan konsep Negara Kesatuan dan Federal yang penulis interpretasikan sebagai
Uni Serikat10
. Negara kesatuan merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat di mana seluruh
negara yang berkuasa hanyalah satu Pemerintah (Pusat) yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan
dapat pula berbentuk dengan sistem Serdang Asliisasi – segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur
dan diurus Pemerintah Pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Negara kesatuan dengan
sistem deSerdang Asliisasi–kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah
tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah swatantra11
. Negara federal digolongkan
dengan apa yang dikenali dengan istilah “prinsip federal”. Prinsip federal adalah cara pembagian
kekuasaan agar tiap pemerintahan umum (pusat) dan regional (daerah) berada dalam suatu lingkungan
yang sederajat. Faktor-faktor yang mendorong kelompok komunitas membentuk sistem pemerintahan
federal adalah (1) untuk mendapat keamanan militer, keuntungan ekonomi dan karena adanya keterikatan
geografis, (2) adanya perbedaan kepentingan ekonomi, perasaan terisolasi karena faktor geografi dan
7Patrick Dunleavy and Bremdan O’Leary, Theories of The State, The Politics of Liberal Democracy,
(London: Macmilan and Education Ltd, 1991), hlm. 1-3. 8Jhon Schwarzmantel, The State in Contemporary Society an Introduction, (New York, London, Toronto,
Sidney, Tokyo, Singapore Harvester Wheatseaf, 1994), hlm. 7-8. 9Ibid, hlm.9 10Negara Uni Serikat merupakan negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh wilayah satu negara
berada pada beberapa wilayah yang menjadi bagian dari negara. Hubungan kekuasaan (kedaulatan) yang disepakati dalam negara ini adalah pembagian dan kerjasama kekuasaan
menurut tingkatan. Artinya wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari negara ini mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur, menentukan dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya.
11C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta : Bumi Aksara, 1985), hlm. 4
4
ketidaksamaan lembaga-lembag sosial dan politik.12
Dengan adanya perbedaan itu, sebuah komunitas
sosial tergerak untuk mempertahankan kemerdekaan regional dalam kesatuan. Masih dalam batasan
konsep federal, Kranenburg13
menyatakan, bahwa negara-negara bagian suatu federasi memiliki
wewenang membentuk undang-undang dasar sendiri serta mengatur bentuk organisasi politik sendiri
dalam batas-batas kostitusi federal. Di samping itu pemerintah federal memiliki hak penuh untuk
masalah hubungan luar negeri dan mencetak uang. Sebaliknya negara bagian mempunyai hak untuk
mengurus masalah kebudayaan, kesehatan dan masalah sosial lainnya yang tidak boleh dicampuri oleh
pemerintah federal.14
Selain memakai pendekatan ekonomi politik, buku ini juga menggunakan pendekatan kesukuan.
Pemakaian konsep ini diharapkan dapat mengungkapkan ketegangan etnis dan konflik yang menyertai
proses perkembangan Negara Negara KeSultanan Serdang.
Geertz menyatakan, bahwa kesukuan adalah sebagian dari ikatan primordial, yang bersifat
kekeluargaan akibat adanya ikatan biologis, seperti keluarga besar, garis keturunan dan sebagainya.
Ikatan primordial itu sendiri diartikan sebagai perasaan yang lahir dari dalam kehidupan sosial
berdasarkan hubungan keluarga, keagamaan, bahasa, dan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Selanjutnya
dijelaskan bahwa adsanya konflik langsung antara ikatan-ikatan primordial dan ikatan-ikatan kebangsaan
mengakibatkan timbulnya gagasan-gagasan kesukuan, kedaerahan, perkauman dan sebagainya.15
Kesukuan akan hadir sebagai dasar menentukan identitas sosial suatu masyarakat mencapai tingkat
kemajekan budaya. Komposisi etnis masyarakat Negara KeSultanan Serdang sebagaiman diperlihatkan
dalam sensun 1930, tidak saja majemuk multietnis dan multiras, tetapi secara mendasar berubah
didominasi kaum pendatang. Tidak berlebihan kiranya apabila Kemala Chandra Kirana16
menyatakan,
bahwa salah satu faktor yang memicu munculnya gerakan Negara Negara KeSultanan Serdang adalah
meluasnya peranan kaum pendatang, terutama dalam penguasaan tanah.
Mengingat banyaknya konflik yang menyertai proses sejarah NEGARA KESULTANAN SERDANG,
perlu dipergunakan teori konflik. Konflik dapat dilihat sebagai interaksi antara dua atau lebih kelompok
kekuatan yang memiliki kepentingan yang berlawanan. Inter aksi akan meningkat menjadi konflik. Jadi
konflik merupakan bentuk paling ekstrem dalam persaingan atau kompetisi.17
Selain itu konflik juga
dapat terjadi karena adanya kepentingan ekonomis, politik dan ideologi. Suatu sistem sosial dikatana
berada dalam keadaan konflik, bila sistem itu mempunyai dua atau lebih tujuan yang saling bertentangan.
Konflik juga dirumuskan sebagai proses perjuangan mencapai nilai dan tuntutan atas status kekuasaan
dan sumber daya yang bertujuan untuk mengatasi, merusak atau menghancurkan saingannya. Secara
konvensional, konflik dirumuskan sebagai kejadian atau peristiwa, pertarungan dengan atau tanpa
kekerasan. Dengan demikian perlu dicari kausalitasnya baik sebab-sebab situasional maupun sebab-
sebab langsung.18
12A. Arthur Chiller, The Formation of Federal Indonesia, (The Hague/Bandung : W. van Hoeve Ltd, 1995) hlm.
25-26 13Kranenburg, Ilmu Negara Umum, (Jakarta : Pradya Paramita, 1983), hlm. 163-168) 14Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia, 1986) hlm. 163-168 15Cliffford Geertz, “Ikatan-ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan di Negara-negara Baru”, dalam
Juwono Sudarsono, (ed), Pembangunan Politik dan Perubahan Politik, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,
1991), hlm. 3-5. 16Kemala Chandra Kirana, “Geertz dan Masalah Kesukuan”, Dalam Prisma No.2 thn. Ke-xviii, (Jakarta : LP3ES,
1989). 17Sebagai rujukan lihat Ralf Dahrendorf, Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Indunstri : Sebuah
Analisis Kritik, (Jakarta : Rajawali Press, 1986), hlm. 191. Anthony Giddens dan David Held, Pendekatan Klasik
dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik, (Jakarta : Rajawali Press, 1987), hlm. 169, 18 Nel J. Smelser, Theory of Collecive Behavior, (New York, The Free Press, 1971), hlm. 169.
5
Di samping itu, karena periode ini masuk dalam masa revolusi nasional, maka perlu dipakati teori
revolusi integratif. Geertz merumuskan revolusi integratif sebagai berhimpunnya kelompok-kelompok
primordial yang tradisional dan berdiri sendiri, ke dalam unit kemasyarakatan yang lebih besar dan
kerangka acuannya bukan lokal, tetapi lingkup bangsa, dalam arti seluruh masyarakat di bawah
perlindungan suatu pemerintahan baru.19
Oleh karen itu revolusi integratif adalah suatu proses yang
memunculkan kelompok-kelompok primordial ini menjadi kesatuan politik yang lebih besar dan
bercabang pengorganisasiannya. Wawasan kelompok primordial ini menjadi lebih luas dari lingkup lokal
ke lingkup negara (nation state) yang supra lokal. Ikatan primordial dalam penjelasan Geertz diperluas
ke tingkat politik nasional. Apa yang sebelumnya merupakan suatu kesatuan politik dengan ukuran kecil,
memiliki otonomi relatif dan bersifat primordial, selanjutnya dianggap terbaur (integrate) ke dalam
kesatuan politik yang tunggal. Ciri-ciri kesatuan yang baru adalah adanya pemisahan antara bidang
kepentingan golongan dengan bidang kepentingan umum berdasarkan kewarganegaraan.
Sementara itu menurut pandangan Liddle20
integrasi nasional memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi
horizontal yaitu masalah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan suku, rasa, agama, aliran dan
sebagainya. Kedua, adalah dimensi vertikal yaitu masalah yang muncul dan berkembang menjadi
terbentuknya jurang, pemisah antara golongan elit nasional yang lebih kecil jumlahnya dengan massa
rakyat yang besar jumlahnya. Kedua dimensi ini menurut pendapatnya mempengaruhi pembentukan
nation state.
5. Telaah Pustaka Bahan–bahan literatur yang kiranya relevan dengan kajian yang akan penulis teliti adalah karya dari
Anthony Reid; The Blood Of The People Revolution And The End Of Traditional Rule In Northern
Sumatra, yang diterjemahkan oleh Tim PSH (Pustaka Sinar Harapan). Dalam karyanya ini hal–hal yang
dapat penulis ambil adalah mengenai kajian dari susunan daulat raja–raja Melayu; dalam karya ini
digambarkan bagaimana keahlian khas raja–raja Melayu dalam menjalin hubungan dengan penduduk
yang suka merompak dan suku–suku lain yang lebih besar jumlahnya tanpa mengorbankan nilai–nilai
adat kebiasaan dari raja–raja Melayu tersebut. Yang lebih penting dalam karya ini juga menggambarkan
pelopor–pelopor revolusi di Sumatera Timur tersebut. Disamping The Blood Of The People Revolution
And The End Of Traditional Rule In Northern Sumatra yang diterjemahkan ini, Revolusi Nasional
Indonesia juga menjadi kerangka analisa utama penulis dalam penulisan buku ini disamping karya–karya
pendukung lainnya.
Karya selanjutnya yang penulis pakai adalah karya dari Tengku Luckman Sinar dalam Sari Sejarah
Serdang. Pada karya ini, penulis merasa terbantu untuk mengerti akan latarbelakang dan mengenai
daerah–daerah yang masuk kedalam wilayah kerajaan Serdang tersebut. Disamping Sari Sejarah
Serdang; Jati Diri Melayu juga penulis pakai karena dengan adanya karya ini penulis lebih memahami
akan budaya politik Melayu yang kiranya membantu penulis dalam memahami akan Negara KeSultanan
Serdang . Selanjutnya tulisan dalam Denyut Nadi Revolusi yang menguraikan disekitar Sumatera Timur
menjelang proklamasi dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Izharry Agusjaya Moenzir dalam Tengku Nurdin : Bara Juang Nyala Di Dada; karya ini menguraikan
bagaimana perjalanan hidup seorang bangsawan revolusioner dari kehidupan dalam istana hingga terjun
langsung kekancah pertempuran untuk mendukung revolusi Indonesia di Sumatera Timur tersebut.
19Clifford Geertz, “The Integrative Revolution Primordial Sentiments and Civil Politic on the
NewState”, dalam Cliffor Geertxz (ed), The Interpretation of Cultures, (New York : Basic Books, 1973), hlm. 106.
20R. William Liddle, Ethnicity, Party and National Integration : An Indonesia Case Study. (Yale University
Press, 1970)
6
Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah cetakan ke–2 oleh Sartono Kartodirdjo; alasan
penulis memilih bahan literatur ini oleh karena penulis untuk memahami penulisan buku ini
membutuhkan salah satu pegangan metodologis dalam hal mempertanggungjawabkan secara ilmiah dari
kajian yang penulis teliti. Dalam karya ini banyak hal yang dapat penulis ambil untuk lebih memperkuat
landasan kajian yang penulis teliti seperti untuk konsep dan perspektif sejarah (Teori dan Metodologi
Sejarah) serta pengertian pendekatan–pendakatan yang dilakukan ilmu sejarah terhadap ilmu–ilmu sosial
lainnya.
Selain karya dari Sartono; penulis juga menggunakan bahan–bahan literatur lain untuk metode dari
penulisan sejarah. Karya yang penulis anggap sangat membantu juga adalah karya–karya sejarah yang di
sunting dari beberapa makalah yang digabungkan kedalam satu karya seperti Pemahaman Sejarah
Indonesia : Sebelum dan Sesudah Revolusi oleh William H. Frederick dan Soeri Soeroto. Dalam karya
ini yang dapat penulis ambil sebagai penambah untuk mengarahkan penulis kiranya menuju kearah
kesempurnaan dalam pengkajian dari permasalahan yang penulis teliti; seperti, empat unsur dalam
pemikiran sejarah yang merupakan proses untuk dapat memahami masa lampau yang umum diakui di
dunia masa kini sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Selain unsur pemikiran sejarah hal–hal
yang penulis ambil dalam karya ini adalah landasan utama daripada metode sejarah; bagian ini
menerangkan bagaimanakah seorang historiograf dalam menangani bukti–bukti yang diyakini sebagai
sesuatu dari bukti sejarah kemudian setelah didapat bukti–bukti tersebut bagaimana menghubungkan dari
satu bukti ke bukti yang lainnya.
Abdul Latiff Abu Bakar dalam Melaka dan Arus Gerak Kebangsaan Malaysia dalam karya ini ada
diungkapkan mengenai budaya politik Melayu; untuk memahami akan budaya Melayu maka sangat
tetaptlah kiranya penulis memakai tulisan Abdul Latiff Abu Bakar ini.
Tim Pengumpulan, Penelitian dan Penulisan Sejarah Perkembangan Pemerintahan DATI I Sumatera
Utara dalam Draf Sejarah Perkembangan Pemerintahan propinsi Sumatera Utara, 1945–1950. Karya ini
menguraikan mengenai hal–hal Sumatera Utara dalam revolusi Indonesia.
Karl J. Pelzer dalam Planter And Peasant, Colonial Policy And The Agrarian Strunggle In East
Sumatera (1863-1947) atau Toen Keboen Dan Petani : Politik Kolonial Dan Perjuangan Agraria Di
Sumatera Timur, 1863–1947 yang diterjemahkan oleh J. Rumbo. Pada karya ini secara luas meguraikan
kehidupan kaum bangsawan setelah kedatangan bangsa asing yang secara tidak langsung
memperkenalkan keberadaan Sumatera timur tersebut.
Selanjutnya tulisan dari Indera dalam Peranan Deli Spoorweg Maatchappij Sebagai Alat Transportasi
Perkebunan Di Sumatera Timur, 1883–1940 dalam Buletin Historisme edisi No. 9 bulan Januari ditahun
1998. Dalam tulisan ini diuraikan bagaimana suatu perusahaan perkebunan dapat membuka kota seperti
kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi dan lain–lain. Disamping karya Peranan Deli Spoorweg Maatchappij
Sebagai Alat Transportasi Perkebunan Di Sumatera Timur, 1883–1940 didalam buletin yang sama di
edisi No. 11 pada bulan Januari ditahun 1999 dengan tulisan Perkebunan Tembakau Deli, 1863–1891
menguraikan bahwa dengan ditemukannya tanaman tembakau yang berkualitas sangat membantu
Sumatera Timur dalam pemasukan devisa ke kas dibanyak negara di Sumatera timur.
George Mc Turnan Kahin dalam Nationalism And Revolution In Indonesia, atau Refleksi Pergumulan
Lahirnya Republik : Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia yang diterjemahkan oleh Nin Bakdi
Soemanto. Dalam karya ini digambarkan bagaimana awal–awal dari revolusi Indonesia sampai
pengakuan kedaulatan Belanda atas keberadaan Indonesia.
Panitia Konfrensi Internasional dalam Denyut Nadi Revolusi Indonesia. Karya ini menguraikan
bagaimana sebenarnya gerakan–gerakan revolusioner yang dilakukan oleh rakyat dalam revolusi
Indonesia yang mewabah diseluruh wilayah Indonesia.
7
Ben Anderson dalam Java In A Time Of Revolution Occuption And resistences, 1944–1946 atau
Revolusi Pemuda : Pendudukan Jepang dan Perlawanan Di Jawa, 1944–1946 yang diterjemahkan oleh
Jiman Rumbo. Dalam karya ini penulis merasa terbantu dalam memahami akan latarbelakang pemuda
menjadi radikal. Karya ini juga menguraikan bagaimana hubungan Tan Malaka melalui persatuan
perjuangannya yang dalam kenyataannya organisasi perjuangan ini dituduh sebagai otak dari tragedi
tahun 1946 di Sumatera.
Biliver Singh dalam Dwifungsi ABRI : The Dual Function Of The Indonesian Armed Forces, atau
Dwifungsi ABRI : Asal–Usul, Aktualisasi dan Implikasinya Bagi Stabilitas dan Pembangunan yang
diterjemahkan oleh Robert Hariono Imam menguraikan bagaimana sebenarnya kelahiran militer dan
peran militer Indonesia dalam politik Indonesia di jaman revolusi, khsususnya kebijakan–kebijakan yang
dibuat oleh angkatan darat.
Ulf Sundhaussen dalam Road To Power : Indonesian Military Politics, 1945–1967 atau Politik Militer
Indonesia : Menuju Dwifungsi ABRI yang diterjemahkan oleh Hasan Basari. Dalam karya ini diuraikan
bagaimana sebenarnya latarbelakang terbentuknya militer Indonesia dan latarbelakang prajurit dan
perwiranya menurut suku, agama, dan latarbelakang didikan militer yang mereka dapatkan tersebut serta
perkembangan militer itu sendiri.
Revolusi yang terjadi di Negara KeSultanan Serdang merupakan gambaran Revolusi yang penuh
dengan konflik. Untuk itu penulis merasa perlu menganalisis peristiwa ini melalui teori konflik. Trio
karya yang dapat menjadi acuan untuk menganalisi permasalahan ini berupa karya dari Ralf Dahrendorf
dalam Class and Class Conflik In Industrial Societiey yang diterjemahkan oleh Ali Mandan dalam
Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri : Sebuah Analisa Kritik. Pada karya ini penulis merasa
terbantu untuk mengerti akan doktrin–doktrin Marxian dilihat dari sudut perubahan historis dan wawasan
sosiologis; strukstur sosial dan perubahan–perubahan sosial, perubahan sosial dan pertentangan kelas,
pertentangan kelas dan revolusi, pemilikan dan kelas sosial; kepentingan kelompok, kelompok–
kelompok yang bertentangan, struktur wewenang negara, peran birokrasi, wewenang politik dan kelas
penguasa. Karya Anthony Giddens dan David Held, Pendekatan Klasik dan Kontemporer Mengenai
Kelompok, Kekuasaan dan Konflik; serta karya dari Nel J. Smelser, Theory of Collecive Behavior.
Konflik dapat dilihat sebagai interaksi antara dua atau lebih kelompok kekuatan yang memiliki
kepentingan yang berlawanan. Inter aksi akan meningkat menjadi konflik. Jadi konflik merupakan
bentuk paling ekstrem dalam persaingan atau kompetisi. Selain itu konflik juga dapat terjadi karena
adanya kepentingan ekonomis, politik dan ideologi. Suatu sistem sosial dikatana berada dalam keadaan
konflik, bila sistem itu mempunyai dua atau lebih tujuan yang saling bertentangan. Konflik juga
dirumuskan sebagai proses perjuangan mencapai nilai dan tuntutan atas status kekuasaan dan sumber
daya yang bertujuan untuk mengatasi, merusak atau menghancurkan saingannya. Secara konvensional,
konflik dirumuskan sebagai kejadian atau peristiwa, pertarungan dengan atau tanpa kekerasan. Dengan
demikian perlu dicari kausalitasnya baik sebab-sebab situasional maupun sebab-sebab langsung.
S.N Eisenstadt dalam Revolution and The Transformation of Societies, yang diterjemahkan oleh
Chandra Johan dalam Revolusi dan Transformasi Dalam Masyarakat. Pada karya ini penulis merasa
terbantu untuk mengerti akan sebab musabab terjadinya revolusi atau perubahan yang revolusioner
dengan mengemukakan kerangka kerja studi perbandingan peradapan. Karya ini di samping memberikan
pandangan baru tentang kekhususan historis dan budaya revolusi sembari menganalisa proses terjadinya
perubahan di dalam peradapan–peradapan besar. Bertumpu pada ajakan itu, Eisenstadt menarik
kesimpulan bahwa perubahan revolusioner cendrung mengambil tempat pada negara–negara kerajaan
feodal dan feodal kerajaan.
Tan Malaka dalam Dari Penjara Ke Penjara pada Jilid 1, menguraikan bagaimana sebenarnya
kehidupan seorang yang berasal dari bangsawan Minangkabau tertarik akan marxisme. Disamping karya
Dari Penjara Ke Penjara pada Jilid 1, penulis juga memakai karya Tan Malaka yang lain yaitu Madilog.
Dalam Madilog ini diuraikan bagaimana sebenarnya Tan Malaka dalam memahami marxisme dan dia
8
melihat bahwa marxis “internasional” yang kiranya tidak cocok dengan alam Indonesia. Dalam karya ini
Tan Malaka mengatakan bahwa “komunis Indonesia sudah tumbuh dari jaman Indonesia kuno dengan
gotong–royong sebagai ciri khas utamanaya”. Dalam pengertian perjuangan kelas Tan Malaka
menguraikan sebagai berikut : “pergerakan revolusioner Indonesia bertumpu pada kerjasama antara
semua kelompok atau golongan yang mempunyai kepentingan bersama untuk mengalahkan musuh–
musuh dari kelompok penentang”.
Notosoetardjo dalam Dokumen–Dokumen Konfrensi Meja Bundar : Sebelum, Sesudah dan
Pembubarannya. Dalam karya ini dapat dilihat gambaran bagaimana sebenarnya kebijakan yang diambil
untuk politik nasional ditahun 1946–1947 baik itu untuk muatan dalam negeri sendiri maupun untuk
kebijakan luar negeri (perjanjian dengan Belanda).
Adnan Buyung Nasution dalam The Aspiration For Constitutional Government In Indonesia : A
Socio–Legal Study Of The Indonesian Konstituante, 1956-1959, atau Aspirasi Pemerintahan
Konstitusional Di Indonesia : Studi Sosio–Legal Atas Konstituante, 1956-1959 yang diterjemahkan oleh
Sylvia Tiwon. Dalam karya ini yang dapat penulis ambil sebagai bahan pengkajian penulis ialah bahwa
karya ini menguraikan mengenai latarbelakang proses ketatanegaraan Indoensia beserta pelaku–pelaku
sejarah yang sangat berperan dalam menyusun ketatanegraan ini. Dalam karya ini juga diungkapkan
bagaimana militer (angkatan darat) dengan mitra sipilnya menyususun undang–undang dasar yang akan
diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia ini.
Seketariat Negara Republik Indonesia dalam 30 Tahun Indonesia Merdeka, dalam karya ini yang
kiranya relevan sebagai bahan yang mendukung pengkajian penulis ini ialah mengenai campur tangan
militer (angkatan darat) dalam kebijakan–kebijakan dari politik nasional yang dibuat oleh mitra sipilnya.
Sudijono Sastoadmodjo dalam Perilaku Politik, dalam karya ini yang dapat penulis ambil sebagai
salah satu bahan dari pengkajian ini ialah mengenai budaya politik Indonesia menurut Lucian Pye yang
dikutip dalam karya ini; disamping itu karya ini lebih membantu penulis dalam memahami akan budaya
politik para elit.
Jon Elster dalam An Introductions To Karl Marx atau Marxisme : Analisis Kritis yang diterjemahkan
oleh Sudarmaji. Pada karya ini penulis merasa terbantu untuk memahami apa sebenarnya marxisme itu.
Samakah marxisme yang diterapkan oleh dunia internasional dengan marxisme yang diterapkan oleh
para revolusioner di Indonesia. Ternyata marxisme yang sampai di Indonesia hanyalah dipakai sebagai
wacana penggerak revolusi Indonesia dan bukan sebagai ideologi yang dilaksanakan untuk selamanya.
Fransz Magnis Suseno dalam Etika Jawa : Sebuah Analisa Filsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa,
dalam karya ini yang penulis ambil hanya untuk sebagai studi banding mengenai antara pemahaman
kekuasaan menurut Jawa dengan pandangan kekuasaan menurut paham Melayu dan dalam karya ini juga
ada ditampilkan pemahaman kekuasaan menurut Barat.
Karya dari Muhammad Abduh dan kawan–kawan dalam Pengantar Sosiologi. Dalam karya ini
dijelaskan bagaimana peranan sosiologi dalam menganalisa masyarakat secara umum maupun secara
khusus.
Karya R. William Liddle, Ethnicity, Party and National Integration : An Indonesia Case Study.
Dalam karya ini dijabarkan bagaimana integrasi nasional memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi
horizontal yaitu masalah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan suku, rasa, agama, aliran dan
sebagainya. Kedua, adalah dimensi vertikal yaitu masalah yang muncul dan berkembang menjadi
terbentuknya jurang, pemisah antara golongan elit nasional yang lebih kecil jumlahnya dengan massa
rakyat yang besar jumlahnya. Kedua dimensi ini menurut pendapatnya mempengaruhi pembentukan
nation state.
Karya Clifford Geertz dalam The Integrative Revolution Primordial Sentiments and Civil Politic on
the NewState. Geertz merumuskan revolusi integratif sebagai berhimpunnya kelompok-kelompok
primordial yang tradisional dan berdiri sendiri, ke dalam unit kemasyarakatan yang lebih besar dan
9
kerangka acuannya bukan lokal, tetapi lingkup bangsa, dalam arti seluruh masyarakat di bawah
perlindungan suatu pemerintahan baru.
Yang terahir karya dari Gorys Keraf dalam Komposisi. Pada karya ini, penulis merasa terbantu untuk
mengerti akan cara–cara mengutip, cara membuat catatan kaki, penerapan catatan kaki dan singkatan
serta penyusunan bibliografi.
6. Metodologi Ilmu sejarah seperti ilmu–ilmu lainnya mempunyai unsur yang merupakan alat untuk mengorganisasi
seluruh tubuh pengetahuannya serta merekontruksi pikiran, yaitu metode sejarah. Kalau metode
berkaitan dengan masalah “bagaimana orang memperoleh pengetahuan” (how to know), metodologi
menyangkut soal “mengetahui bagaimana harus mengetahui” (to know how to know). Secara implisit
metodologi mengandung unsur teori.21
Dalam metode sejarah terdapat empat unsur pemikiran sejarah yang merupakan proses untuk
memahami masa lampau; diakui umum di dunia masa kini sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan
yaitu waktu, fakta (bisa juga kenyataan), tekanan pada sebab–musabab dan tidak lagi membatasi
wilayah penyelidikan. Ada sebuah pernyataan yang baik memberikan indikasi dalam persoalan ini : “Dalam metode sejarah ini terdapat empat unsur pemikiran sejarah yang merupakan proses untuk
memahami masa lampau; diakui umum di dunia masa kini sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan.
Yang paling penting ialah pengertian waktu (barangkali harus mengatakan waktu) sebagai sesuatu yang
langgeng dan berurutan. Para ahli sejarah kontemporer memandang waktu dan berlalunya waktu dengan
kecepatan yang teratur dan yang dapat diukur, sebagai pangkal pemikiran sejarah oleh karena waktu dan
ciri-ciri khasnya itu dapat diuraikan sebagai sesuatu yang mutlak dalam sejarah. Kejadian hanya terjadi
satu kali dan satu atau dua kejadian hanya dapat mempunyai satu kaitan dalam waktu. Apa lagi, waktu
juga merupakan suatu segi masa lampau yang dapat kita ukur secara tepat. Seorang sejarahwan moderen
haruslah dapat mengerti secermat mungkin kapan kejadian itu terjadi dan apa kaitannya dengan kejadian
yang lain dalam waktu yang bersamaan atau berurutan. Dalam ukuran yang lebih besar atau lebih kecil
“kerangka besi” ini membentuk segala segi yang menyangkut tafsiran modern tentang masa lampau. Inilah
perbedaan yang antara pandangan moderen yang pengamatan pra atau non–moderen. Unsur selanjutnya
yang harus dipertimbangkan oleh sejarahwan modren ialah kesadaran akan sifat dasar fakta–fakta; yaitu
kerumitannya. Dalam bahasa umum kata fakta (“fact”) atau bisa juga : kenyataan, mengandung kepastian
yang diterima begitu saja. Tapi ahli sejarah moderen sadar akan “kelicinan” fakta. Yang paling sederhana
sekalipun merupakan “fakta”, umpamanya; bahwa sebatang potlot dilihat dari satu sudut pandangan
tanpak panjang dan tipis. Tapi bilamana kita putar potlot itu sehingga kita lihat dari ujung ke ujung
ternyata bentuknya berlainan sama sekali. Kita pun bisa “tergoda” untuk mengatakan suatu pernyataan
yang mencakup berbagai “fakta”. misalnya orang tua Soekarno adalah guru sekolah yang miskin dengan
penghasilan hanya sekian rupiah sebulan. Fakta–fakta itu dapat digunakan untuk memperoleh kesimpulan
yang menyesatkan bila kita tidak menegaskan bahwa penghasilan yang sekian rupiah itu serta status
pekerjaan seorang guru sekolah, menempatkan keluarga Soekarno dalam golongan masyarakat teratas
yang berjumlah 2–3 persen pada waktu itu. Singkatnya, fakta tidak atau jarang sekali merupakan bahan
keterangan yang abstrak dan mutlak. Fakta itu harus dilihat dari berbagai sudut sebanyak mungkin, serta
diperlakukan dengan berhati–hati sekali. Segi lainnya dari fakta yang seharusnya diperhatikan oleh
sejarahwan secara khusus; bahwa yang disebut “fakta” atau “data” murni harus ditanggapi dengan penuh
perhatian, sama seperti halnya dengan. Unsur ketiga yang merupakan ciri khas pemikiran sejarah
moderen ialah tekanan pada sebab–musabab. Para ahli sejarah masa kini ingin mengetahui sejelas–
jelasnya bukan saja kapan suatu kejadian itu terjadi, apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bagaimana
terjadinya, tetapi juga mengapa. Di sini, masalah yang dihadapi memang tidak sekongkrit masalah waktu
atau fakta. Meskipun demikian pemecahannya tidak dapat dilakukan secara serampangan. Sejarah
21Sartono. Op. Cit. , hal. ix.
10
moderan mempunyai metode untuk membimbing penyelidikan dan mempertimbangkan buktinya.
Penggunaan metode ini dinyatakan dengan dua pendekatan terhadap pernyataan tentang sebab–musabab
dalam sejarah. Pertama : ada perbedaan antara “hubungan” dan “sebab”. Bisa saja ada hubungan
(dalam waktu); tetapi tanpa bukti tambahan, maka penulis tidak dapat mengusulkan bahwa antara kedua
kejadian itu ada kaitan penyebabnya. Kedua : para ahli sejarah masa kini menerima pendapat bahwa
pada umumnya kejadian–kejadian mempunyai banyak penyebab; bukan hanya satu. Penyebab–penyebab
itu dapat disusun sedemikian rupa sehingga terlihat bagaimana sesungguhnya mereka saling
mempengaruhi. Akhirnya; sejarah dewasa ini, tidak lagi membatasi wilayah penyelidikannya. Pada
hakekatnya, setiap topik yang dapat dibayangkan manusia dapat dilihat dari sudut sejarah. Semakin
banyak ahli sejarah mengkhususkan diri dalam bidang yang mungkin kedengarannya sempit dan aneh,
sebagai contoh; kebudayaan popular–termasuk nyanyian–nyanyian rakyat dan film. Untuk selanjutnya
terpulang kepada penulis untuk mewujudkan apa sebenarnya arti dari topik semacam itu”22
Sebagai permasalahan inti dari metodologi dalam ilmu sejarah dapat disebut masalah pendekatan.
Penggambaran kita mengenai suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan; ialah dari segi mana
kita memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan dan lain
sebagainya. Hasil pelukisan akan sangat ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai. Dalam
menghadapi gejala historis yang serba kompleks, setiap penggambaran atau debuku menuntut adanya
pendekatan yang memungkinkan penyaringan data yang diperlukan. Suatu seleksi akan dipermudah
dengan adanya konsep-konsep yang berfungsi sebagai criteria.23
Secara sederhana untuk merekontruksi peristiwa yang penulis teliti ini dilakukan dalam beberapa
langkah; yaitu : heuristik, kritik, interprestasi dan historiografi.
Pada tahap heruistik; penelusuran dan pengumpulan bahan data penulis lakukan dengan melalui
teknik quota sampling. Dalam teknik ini jumlah populasi tidak penulis perhitungkan, akan tetapi
dilkasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah atau quotum
tertentu pada setiap kelompok yang seolah–olah berkedudukan masing–masing sebagai sub populasi.
Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling yang penulis temui. Setelah jumlahnya
diperkirakan oleh penulis mencukupi, pengumpulan data dihentikan. Bahan–bahan yang digunakan
adalah bahan–bahan yang berhasil penulis kumpulkan melalui sumber–sumber tertulis; dalam hal
pengumpulan sumber–sumber tertulis ini penulis menekankan pada penggunaan studi pustaka atau
library research sebagai pengumpulan sumber utama sejarah yang penulis kaji ditambah dengan hasil
wawancara dengan beberapa tokoh yang terlibat baik secara langsung maupun tokoh–tokoh yang terlibat
secara tidak langsung pada peristiwa sejarah tersebut.
Adapun tokoh–tokoh yang penulis wawancarai itu adalah sebagai berikut :
1) Almarhum Bapak Tengku Luckman Sinar, SH. merupakan seorang anak dari almarhum Sultan
Serdang. Sekarang pernah berkedudukan sebagai pewaris dari Dewan Negara KeSultanan
Serdang . Bapak ini berumur kira–kira 50 Tahun (sewaktu Penulis Wawancarai di tahun 2001)
dan tinggal di Jalan Abdulla Lubis No. 42/47 Medan;
2) Bapak Tengku Syahrial. Bapak ini juga merupakan salah seorang anak dari almarhum Sultan
Serdang. Pada masa revolusi Indonesia, bapak ini menggabungkan diri kedalam TRI dan juga
sebagai Seketaris dari Jenderal Timur Pane. Bapak ini berumur kira–kira 80 Tahun dan sekarang
beralamat di Jalan Kalimantan III No. 18 B Kompleks Perumahan Pelabuhan, km 20 Belawan;
3) Bapak Tengku Syahrul. Bapak ini merupakan salah seorang bangsawan Melayu Langkat.
Sewaktu revolusi Indonesia terjadi bapak ini masih berumur kira–kira 5 tahun dan masih
mengingat kejadian–kejadian diseputar revolusi Indonesia di Langkat. Bapak ini berumur kira–
kira 61 tahun dan sekarang beralamat di Jalan Fatahila No.12 Selesai;
22Frederick, Soeri Soeroto. Pemahaman Sejarah Indonesia : Sebelum dan Sesudah Revolusi (Jakarta :
LP3ES, 1991), hal. 7–13. 23Sartono. Op. Cit., hal.4.
11
4) Bapak Tengku Muhammad Abra. Bapak ini merupakan salah seorang bangsawan Melayu Deli.
Sewaktu revolusi Indonesia terjadi bapak ini masih berumur kira–kira 5 tahun dan masih
mengingat kejadian–kejadian diseputar revolusi Indonesia di Deli; dimana pada waktu revolusi
sosial 1946 istana Maimun diserang oleh kelompok sipil bersenjata yang anti–feodal. Bapak ini
berumur kira–kira 60 tahun dan sekarang beralamat di Jalan Lampu Kompleks Rispa No.15
Medan.
Dari jawaban–jawaban informan atas dasar pengalaman dan pendapat mereka lalu diperiksa berselang
lagi dengan informan lainnya. Misalnya mengenai bagaimanakah sebenarnya Negara KeSultanan
Serdang dalam memahami revolusi Indonesia di Sumatera Timur itu dari keanekaragaman dan
pertumbuhannya yang dinamis serta subur tersebut dan mengenai seperti apa bentuk/tampilan yang
digunakan Negara KeSultanan Serdang dalam revolusi Indonesia di Sumatera Timur itu. Pada tahap ini
penulis telah melakukan penelitian terhadap bahan-bahan koleksi dari Almarhum bapak Tengku
Lukcman Sinar, SH; buku–buku koleksi dari perpustakaan USU, buku–buku koleksi pribadi dari milik
teman penulis - Mahardi dan buku–buku koleksi penulis pribadi. Tindakan yang akan penulis lakukan ini
sesuai dengan tahapan kedua dari metode sejarah yakni merekonstruksi peristiwa ini dengan mengadakan
kritikan terhadap sumber–sumber data yang telah penulis kumpulkan dan yang kemudian berdasarkan
kebutuhan objek peneltian selanjutnya di seleksi.
Setelah sumber–sumber data yang terseleksi ini; maka tindakan selanjutnya yang penulis lakukan
ialah mengadakan interprestasi terhadap sumber–sumber data tersebut untuk menemukan struktur logis
dengan kebutuhan sumber–sumber data yang mendukung peristiwa ini sehingga mempunyai makna.
Akhirnya dengan kombinasi langkah–langkah yang sebelumnya penulis lakukan; maka barulah
diketengahkan tulisan ini ke khalayak pembaca melalui suatu bentuk laporan penelitian.
7. Pertanggung Jawaban Sistematika
Selanjutnya pembicaraan mengenai buku ini akan dibentangkan dalam enam bab, yang masing-
masing dibagi lagi dalam sub-bab. Bab Satu yang berupa pendahuluan daripada bagian ini berisi
diseputar latar belakang situasi dan kondisi yang menyertai dinamika NEGARA KESULTANAN
SERDANG.
Bab Dua berisi bagaimana proses gambaran umum Negara Kesultanan Serdang dengan melihat dari
segi kondisi geografis negara, titik awal keberadaan Negara, kondisi ekonomi-politik negara dan
bagaimana sebenarnya penduduk yang mendiami Negara Kesultanan Serdang ini. memperkokoh negara
Bab Tiga akan dibahas mengenai bagaimana untuk memperkokoh NEGARA KESULTANAN
SERDANG, mengingat posisi strategis daripada Sumber Hukum Materiil Daulat-Durhaka, Sumber
Hukum Formal serta Asas Pembagian dan Kerjasama Kekuasaan.
Bab Empat akan membahas mengenai perihal Bentuk dan Sistem Negara yang diterapkan oleh Negara
KeSultanan Serdang. Dalam bab ini dijabarkan tentang masalah-masalah diseputar : Ciri-Ciri Negara
Negara KeSultanan Serdang, Sifat-Sifat Negara, Unsur-Unsur Negara, Wilayah, Tujuan dan Fungsi
Negara, Kependudukan, Falsafah Negara Serdang : Adil di Sembah – Zalim di Sanggah dan Dasar
Negara Kesultanan Serdang.
Bab Lima; dalam bagian ini akan membahas mengenai hal Bentuk dan Sistem Pemerintahan.
Penjabaran pada bagian ini akan tertuju diseputar : Kelahiran dan Evolusi Pemerintahan, Bentuk
Pemerintahan, Susunan Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan.
Bab Enam merupakan sebagai bagian penutup akan memberikan simpulan secara umum diseputar
Konstruksi Negara Kesultanan Serdang berdasarkan perjalanan daripada Negara Kesultanan Serdang
tersebut.