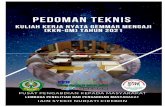Kesultanan Cirebon
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Kesultanan Cirebon
LAPORAN KEGIATAN
PRAKTIKUM LAPANGAN KE KESULTANAN CIREBON
Diajukan untuk memenuhi tugas individu Kuiah Kerja
Lapangan ke-1
oleh
Elis Setiawati
NIM 1305099
2B
PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2014
PENDAHULUAN
Dalam rangka praktikum lapangan (kuliah lapangan)
yang dilaksanakan pada Sabtu, 17 Mei 2014 ke Keraton
Kasepuhan Cirebon merupakan praktikum pertama yang
dilaksanakan untuk mahasiswa Pendidikan Sosiologi UPI
angkatan 2013. Dalam praktikum lapangan ini setidaknya
kami mengunjungi dua tempat yang memiliki ciri khas dan
keistimewaan tersendiri di daerah Cirebon, yaitu
Keraton Kasepuhan Cirebon yang berada tidak jauh dari
Kota Cirebon dan desa adat yang berada di Dusun
Keputihan, Desa Kertasari, Kecamatan Weru Kabupaten
Cirebon. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi salah
satu kontrak mata kuliah praktikum lapangan yang
dilaksanakan setiap tahunnya untuk tiap angkatan
masing-masing.
Kegiatan ini tidak semata-mata hanya untuk
memenuhi kontrak mata kuliah saja atau sekedar
praktikum lapangan untuk mengetahui masyarakat kota
tersebut, tetapi dengan adanya praktikum ini kita dapat
mengenal dan mengamati masyarakat Cirebon secara
langsung. Dengan terjun langsung ke lapangan setidaknya
dapat memberikan pemahaman tentang kehidupan masyarakat
khususnya di Keraton Kasepuhan cirebon dan umumnya
masyarakat luas.
Dengan adanya praktikum lapangan ke Keraton
Kasepuhan Cirebon, kita dapat mengetahui seluk beluk
wilayah Keraton Kasepuhan Cirebon, sejarah berdirinya
keraton, adat istiadat atau tradisi yang dilaksanakan
setiap tahunnya di keraton, dan banyak hal lain
sebagainya.
LAPORAN KEGIATAN PRAKTIKKUM LAPANGAN KE KERATON
KASEPUHAN CIREBON
A. Kesultanan Cirebon
1. Sejarah Singkat Kesultanan Cirebon
Kesultanan Cirebon adalah sebuah kerajaan islam yang
ternama di Jawa Barat. Kerajaan ini berkuasa pada abad
ke 15 hingga abad ke 16 M. Letak kesultanan cirebon
adalah di pantai utara pulau jawa. Lokasi perbatasan
antara jawa tengah dan jawa barat membuat kesultanan
Cirebon menjadi “jembatan” antara kebudayaan jawa dan
Sunda. Sehingga, di Cirebon tercipta suatu kebudayaan
yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak
didominasi oleh kebudayaan Jawa maupun kebudayaan
Sunda.
Pada awalnya, cirebon adalah sebuah dukuh kecil yang
dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Demikian dikatakan oleh
serat Sulendraningrat yang mendasarkan pada naskah
Babad Tanah Sunda. Lama-kelamaan cirebon berkembang
menjadi sebuah desa yang ramai yang diberi nama
caruban. Diberi nama demikian karena di sana bercampur
para pendatang dari beraneka bangsa, agama, bahasa, dan
adat istiadat.
Karena sejak awal mata pecaharian sebagian besar
masyarakat adalah nelayan, maka berkembanglah pekerjaan
nenangkap ikan dan rebon (udang kecil) di sepanjang
pantai, serta pembuatan terasi, petis dan garam. Dari
istilah air bekas pembuatan terasi (belendrang) dari
udang rebon ini berkembang sebutan cai-rebon (bahasa
sunda : air rebon), yang kemudian menjadi cirebon.
Dengan dukungan pelabuhan yang ramai dan sumber daya
Alam dari pedalaman, cirebon menjadi salah satu
pelabuhan penting di pesisir utara jawa. Dari pelaburan
cirebon, kegiatan pelayaran dan perniagaan berlangsung
antar-kepulauan nusantara maupun dengan bagian dunia
lainnya. Selain itu, tidak kalah dengan kota-kota
pesisir lainnya Cirebon juga tumbuh menjadi pusat
penyebaran islam di jawa barat.
Alkisah, hiduplah Ki gedeng Tapa, seorang saudagar
kaya di pelabuhan Muarajati. Ia mulai membuka hutan,
membangun sebuah gubuk pada tanggal 1 Sura 1358 (tahun
jawa), bertepatan dengan tahun 1445 M. Sejak saat itu,
mulailah para pendatang menetap dan membentuk
masyarakat baru di desa caruban. Kuwu atau kepala desa
pertama yang diangkat oleh masyarakat baru itu adalah
Ki Gedeng Alang-alang. Sebagai pangraksabumi atau
wakilnya, diangkatlah raden Walangsungsang.
Walangsungsang adalah putra prabu Siliwangi dan Nyi Mas
Subanglarang atau Subangkranjang, putri Ki Gedeng Tapa.
Setelah ki gedeng alang-alang meninggal walangsungsang
bergelar Ki Cakrabumi diangkat sebagai Kuwu pengganti
ki Gedeng Alang-alang dengan gelar pangeran Cakrabuana.
Ketika kakek ki gedeng Tapa meninggal, pangeran
cakrabuana tidak meneruskannya, melainkan mendirikan
istana Pakungwati, dan membentuk pemerintahan cirebon.
Dengan demikian yang dianggap sebagai pendiri pertama
kesultanan Cirebon adalah pangeran Cakrabuana (…. –
1479). Seusai menunaikan ibadah haji, cakrabuana
disebut Haji Abdullah Iman, dan tampil sebagai raja
Cirebon pertama yang memerintah istana pakungwati,
serta aktif menyebarkan islam.
Pada tahun 1479 M, kedudukan Cakrabuana digantikan
oleh keponakannya. Keponakan Cakrabuana tersebut
merupakan buah perkawinan antara adik cakrabuana, yakni
Nyai Rarasantang, dengan Syarif Abdullah dari Mesir.
Keponakan Cakrabuana itulah yang bernama Syarif
Hidayatullah (1448 – 1568 M). Setelah wafat, Syarif
Hidayatullah dikenal dengan nama sunan Gunung Jati,
atau juga bergelar ingkang Sinuhun Kanjeng Jati Purba
Penetep Panatagama Awlya Allah Kutubid Jaman
Khalifatura Rasulullah.
Pertumbuhan dan perkembangan kesultanan Cirebon yang
pesat dimulai oleh syarif Hidayatullah. Ia kemudian
diyakini sebagai pendiri dinasti kesultanan cirebon dan
banten, serta menyebar islam di majalengka, Kuningan,
kawali Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Setelah Syarif
Hidayatullah wafat pada tahun 1568, terjadilah
kekosongan jabatan pimpinan tertinggi kerajaan Islam
cirebon. Pada mulanya, calon kuat penggantinya adlah
pangeran Dipati Carbon, Putra Pengeran Pasarean, cucu
syarif hidayatullah. Namun, Pangeran dipati carbon
meninggal lebuh dahulu pada tahun 1565.
Kosongnya kekuasaan itu kemudian diisi dengan
mengukuhkan pejabat istana yang memegang kenali
pemerintahan selama syarif Hidayatullah atau Sunan
Gunung Jati melaksanakan Dakwah. Pejabat tersebut
adalah Fatahillah atauFadillah Khan. Fatahillah
kemudian naik tahta, secara resmi menjadi sultan
cirebon sejak tahun 1568.
Naiknya Fatihillah dapat terjadi karena dua
kemungkinan pertama, para sultan Gunung Jati, yaitu
Pangeran Pasarean, pangeran Jayakelana, dan pangeran
Bratakelana, meninggal lebih dahulu, sedangkan putra
yang masih hidup, yaitu sultan Hasanuddin (pangeran
Sabakingkin), memerintah di Banten berdiri sendiri
sejak tahun 1552 M. Kedua, Fatahillah adalah menantu
Sunan Gunung Jati (Fatahillah menikah dengan Ratu Ayu,
putri sunan Gunung Jati), dan telah menunjukkan
kemampuannya dalam memerintah Cirebon (1546 – 1568)
mewakili Sunan Gunug Jati. Sayang, hanya dua tahun
Fatahillah menduduki tahta Cirebon, karena ia meninggal
pada 1570.
Sepeninggal Fatahillah, tahta jatuh kepada cucu
Sunan Gunung Jati, yaitu pangeran Emas. Pangeran emas
kemudian bergelar panembahan ratu I, dan memerintah
cirebon selama kurang lebih 79 tahun. Setelah
panembahan ratu I meninggal pada tahun 1649,
pemerintahan kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh
cucunya yang bernama pangeran Karim, karena ayahnya
yaitu panembahan Adiningkusumah meninggal dunia
terlebih dahulu. Selanjutnya, pangeran karim dikenal
dengan sebutan Panembahan Ratu II atau panembahan
Girilaya.
Pada masa pemerintahan Panembahan Girilaya, Cirebon
terjepit di antara dua kekuatan, yaitu kekuatan Banten
dan kekuatan mataram. Banten curiga, sebab cirebot
dianggap mendekat ke mataram. Di lain pihak, mataram
pun menuduh cirebon tidak lagi sungguh-suingguh
mendekatkan diri, karena panembahan Girilaya dan Sultan
Ageng dari banten adalah sama-sama keturunan pajajaran.
Kondisi panas ini memuncak dengan meninggalnya
panembahan Girilaya saat berkunjung ke Kartasura. Ia
lalu dimakamkan di bukit Girilaya, Gogyakarta, dengan
posisi sejajar dengan makam sultan Agung di Imogiri.
Perlu diketahui, panembahan Girilaya adalah juga
menantu Sultan Agung Hanyakrakusuma. Bersamaan dengan
meninggalnya panembahan Girilaya, Pangeran Martawijaya
dan Pangeran Kartawijaya, yakni para putra panembahan
Girilaya di tahan di mataram.
Dengan kematian panembahan Girilaya, terjadi
kekosongan penguasa. Sultan ageng tirtayasa segera
dinobatkan pangeran Wangsakerta sebagai pengganti
panembahan Girilaya, atas tanggung jawab pihak Banten.
Sultan ageng tirtayasa pun kemudian mengirimkan pasukan
dan kapal perang untuk membantu trunajaya, yang pada
saat itu sedang memerangi Amangkurat I dari mataram.
Dengan bantuan Trunajaya, maka kedua putra penembahan
Girilaya yang ditahan akhirnya dapat dibebaskan, dan
dibawa kembali ke Cirebon. Bersama satu lagi putra
panembahan Girilaya, mereka kemudian dinobatkan sebagai
penguasa kesultanan Cirebon.
Panembahan Girilaya memiliki tiga putra, yaitu
pangeran murtawijaya, pangeran Kartawijaya, dan
pangeran wangsakerta. Pada penobatan ketiganya di tahun
1677, kesultanan cirebon terpecah menjadi tiga. Ketiga
bagian itu dipimpin oleh tiga anak panembahan Girilaya,
yakni :
1. Pangeran Martawijaya atau sultan Kraton Kasepuhan,
dengan gelar Sepuh Abi Makarimi Muhammad Samsudin (1677
– 1703)
2. Pangeran Kartawijaya atau Sultan Kanoman, dengan
gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badrudin (1677
– 1723)
3. Pangeran Wangsakerta atau Panembahan Cirebon, dengan
gelar pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasarudin atau
Panembahan Tohpati (1677 – 1713)
Perubahan gelar dari “panembahan” menjadi “sultan”
bagi dua putra tertua pangeran girilaya dilakukan oleh
Sultan Ageng Tirtayasa. Sebab, keduanya dilantik
menjadi sultan Cirebon di Ibukota banten. Sebagai
sultan, mereka mempunyai wilayah kekuasaan penuh,
rakyat, dan keraton masing-masing. Adapun pangeran
wangsakerta tidak diangkat sebagai Sultan, melainkan
hanya panembahan. Ia tidak memiliki wilayah kekuasaan
atau keraton sendiri, akan tetapi berdiri sebagai
kaprabonan (paguron), yaitu tempat belajar para ilmuwan
keraton.
Pergantian kepemimpinan para sultan di cirebon
selanjutnya berjalan lancar, sampai pada masa
pemerintahan Sultan Anom IV (1798 – 1803). Saat itu
terjadilah pepecahan karena salah seorang putranya,
yaitu pangeran raja kanoman, ingin memisahkan diri
membangun kesultanan sendiri dengan nama kesultanan
Kacirebonan.
Kehendak raja kanoman didukung oleh pemerintah
belanda yang mengangkatnya menjadi Sultan Cirebon pada
tahun 1807. namun belanda mengajukan satu syarat, yaitu
agar putra dan para pengganti raja Kanoman tidak berhak
atas gelar sultan. Cukup dengan gelar pangeran saja.
Sejak saat itu, di Kesultanan Cirebon bertambah satu
penguasa lagi, yaitu kesultanan Kacirebonan. Sementara
tahta sultan Kanoman V jatuh pada putra Sultan Anom IV
lain bernama Sultan Anom Abusoleh Imamuddin (1803 –
1811).
Sesudah kejadian tersebut, pemerintah kolonial
belanda pun semakin ikut campur dalam mengatur Cirebon,
sehingga peranan istana-istana kesultanan Cirebon di
wilayah-wilayah kekuasaannya semakin surut. Puncaknya
terjadi pada tahun-tahun 1906 dan 1926, ketika
kekuasaan pemerintahan kesultanan Cirebon secara resmi
dihapuskan dengan pengesahan berdirinya Kota Cirebon.
B. Keraton Kasepuhan Cirebon
1. Sejarah Keraton kasepuhan Cirebon
Pada abad XV (± tahun 1430) Pangeran Cakrabuana,
putra mahkota Padjajaran membangun kraton yang kemudian
diserahkan kepada putrinya, Ratu Ayu Pakungwati, maka
kratonnya dinamai Kraton Pakungwati (hingga sekarang
dikenal dengan sebutan Dalem Agung Pakungwati).
Ratu Ayu Pakungwati kemudian menikah dengan
sepupunya Syekh Syarif Hidayatullah (putra Ratu Mas
Lara santang adik Pangeran Cakrabuana) lebih dikenal
dengan sebutan Sunan Gunung Jati, kemudian Sunan Gunung
Jati dinobatkan sebagai Pimpinan atau Kepala Negara di
Cirebon dan bersemayam di Kraton Pakungwati. Semenjak
itu Cirebon merupakan pusat pengembangan Agama Islam di
Jawa dengan adanya WaliSanga yang dipimpin Sunan Gunung
Jati dan peninggalan-peninggalannya diantaranya Masjid
Agung Sang Cipta Rasa.
Pada abad XVI Sunan Gunung Jati wafat, kemudian
Pangeran Emas Moch. Arifin cicit dari Sunan Gunung Jati
bertahta menggantikannya. Kemudian pada tahun candra
sangkala Tunggal tata Gunaning wong atau 1451 Saka
yaitu tahun 1529 beliau mendirikan kraton baru
disebelah barat daya Dalem Agung Pakungwati, kraton ini
dinamai Kraton Pakungwati dan beliaupun bergelar
Panembahan Pakungwati I.
Kraton Pakungwati mengambil dari nama Ratu Ayu
Pakungwati putri Pangeran Cakrabuwana yang menikah
dengan Sunan Gunung Jati. Putrid ini cantik rupawan,
penyayang rakyat, berbudi luhur dan dapat mendampingi
suami di bidang pembinaan Negara dan Agama.
Pada tahun kurang lebih 1549 M, masjid Agung Sang
Cipta Rasa kebakaran, Ratu Ayu Pakungwati yang sudah
tua itu turut memadamkan api, api dapat dipadamkan
namun Ratu Ayu Pakungwati kemudian wafat. Semenjak itu
nama/sebutan Pakungwati dimuliakan dan diabadikan oleh
nasab Sunan Gunung Jati.
Pada tahun kurang lebih 1679 M didirikan Kraton
Kanoman oleh Sultan Anom I (Sultan Badridin) maka
semenjak itu Kraton Pakungwati disebut Kraton Kasepuhan
hingga sekarang dan sultannya bergelar Sultan Sepuh.
Kasepuhan artinya tempat yang sepuh/tua, jadi antara
Kasepuhan dan Kanoman itu awalnya yang tua dan yang
muda (kakak beradik).
Lokasi bangunan Kraton Kasepuhan membujur dari utara
ke selatan atau menghadap ke utara, karena kraton-
kraton di Jawa semuanya menghadap ke Utara artinya
menghadap magnet dunia, arti falsafahnya Sang Raja
mengharapkan kekuatan.
Di depan Keraton Kesepuhan terdapat alun-alun yang
pada waktu zaman dahulu bernama Alun-alun Sangkala
Buana yang merupakan tempat latihan keprajuritan yang
diadakan pada hari Sabtu atau istilahnya pada waktu itu
adalah Saptonan. Dan di alun-alun inilah dahulunya
dilaksanakan berbagai macam hukuman terhadap setiap
rakyat yang melanggar peraturan seperti hukuman cambuk.
Di sebelah barat Keraton kasepuhan terdapat Masjid yang
cukup megah hasil karya dari para wali yaitu Masjid
Agung Sang Cipta Rasa.
Sedangkan di sebelah timur alun-alun dahulunya
adalah tempat perekonomian yaitu pasar -- sekarang adalah
pasar kesepuhan yang sangat terkenal dengan pocinya. Model bentuk
Keraton yang menghadap utara dengan bangunan Masjid di
sebelah barat dan pasar di sebelah timur dan alun-alun
ditengahnya merupakan model-model Keraton pada masa itu
terutama yang terletak di daerah pesisir. Bahkan sampai
sekarang, model ini banyak diikuti oleh seluruh
kabupaten/kota terutama di Jawa yaitu di depan gedung
pemerintahan terdapat alun-alun dan di sebelah baratnya
terdapat masjid.
Sebelum memasuki gerbang komplek Keraton Kasepuhan
terdapat dua buah pendopo, di sebelah barat disebut
Pancaratna yang dahulunya merupakan tempat berkumpulnya
para punggawa Keraton, lurah atau pada zaman sekarang
disebut pamong praja. Sedangkan pendopo sebelah timur
disebut Pancaniti yang merupakan tempat para perwira
keraton ketika diadakannya latihan keprajuritan di
alun-alun.
Memasuki jalan kompleks Keraton di sebelah kiri
terdapat bangunan yang cukup tinggi dengan tembok bata
kokoh disekelilingnya. Bangunan ini bernama Siti Inggil
atau dalam bahasa Cirebon sehari-harinya adalah lemah
duwur yaitu tanah yang tinggi. Sesuai dengan namanya
bangunan ini memang tinggi dan nampak seperti kompleks
candi pada zaman Majapahit. Bangunan ini didirikan pada
tahun 1529, pada masa pemerintahan Syekh Syarif
Hidayatullah (Sunan Gunung Jati).
Di pelataran depan Siti Inggil terdapat meja batu
berbentuk segi empat tempat bersantai. Bangunan ini
merupakan bangunan tambahan yang dibuat pada tahun
1800-an. Siti Inggil memiliki dua gapura dengan motif
bentar bergaya arsitek zaman Majapahit. Di sebelah
utara bernama Gapura Adi sedangkan di sebelah selatan
bernama Gapura Banteng. Dibawah Gapura Banteng ini
terdapat Candra Sakala dengan tulisan Kuta Bata Tinata Banteng
yang jika diartikan adalah tahun 1451.
Saka yang merupakan tahun pembuatannya (1451 saka =
1529 M). Tembok bagian utara komplek Siti Inggil masih
asli sedangkan sebelah selatan sudah pernah mengalami
pemugaran/renovasi. Di dinding tembok kompleks Siti
Inggil terdapat piring-piring dan porslen-porslen yang
berasal dari Eropa dan negeri Cina dengan tahun
pembuatan 1745 M. Di dalam kompleks Siti Inggil
terdapat 5 bangunan tanpa dinding yang memiliki nama
dan fungsi tersendiri. Bangunan utama yang terletak di
tengah bernama Malang Semirang dengan jumlah tiang
utama 6 buah yang melambangkan rukun iman dan jika
dijumlahkan keseluruhan tiangnya berjumlah 20 buah yang
melambangkan 20 sifat-sifat Allah SWT. Bangunan ini
merupakan tempat sultan melihat latihan keprajuritan
atau melihat pelaksanaan hukuman. Bangunan di sebelah
kiri bangunan utama bernama Pendawa Lima dengan jumlah
tiang penyangga 5 buah yang melambangkan rukun islam.
Bangunan ini tempat para pengawal pribadi
sultan.Bangunan di sebelah kanan bangunan utama bernama
Semar Tinandu dengan 2 buah tiang yang melambangkan Dua
Kalimat Syahadat. Bangunan ini adalah tempat penasehat
Sultan/Penghulu. Di belakang bangunan utama bernama
Mande Pangiring yang merupakan tempat para pengiring
Sultan, sedangkan bangunan disebelah mande pangiring
adalah Mande Karasemen, tempat ini merupakan tempat
pengiring tetabuhan/gamelan. Di bangunan inilah sampai
sekarang masih digunakan untuk membunyikan Gamelan
Sekaten (Gong Sekati), gamelan ini hanya dibunyikan 2
kali dalam setahun yaitu pada saat Idul Fitri dan Idul
Adha. Selain 5 bangunan tanpa dinding terdapat juga
semacam tugu batu yang bernama Lingga Yoni yang
merupakan lambing dari kesuburan. Lingga berarti laki-
laki dan Yoni berarti perempuan. Bangunan ini berasal
dari budaya Hindu. Dan di atas tembok sekeliling
kompleks Siti Inggil ini terdapat Candi Laras untuk
penyelaras dari kompleks Siti Inggil ini.
2. Silsilah Sultan Kasepuhan Cirebon
1. Sunan Gunung Jati (Syarief Hidayatullah)
2. P. Adipati Pasarean (P. Muhammad Arifin)
3. P. Dipati Carbon (P. Sedang Kamuning)
4. Panembahan Ratu Pakungwati I (P. Emas Zainul
Arifin)
5. P. Dipati Carbon II (P. Sedang Gayam)
6. Panembahan Ratu Pakungwati II (Panembahan
Girilaya)
7. P. Syamsudin Martawidjaja (Sultan Sepuh I)
8. P. Djamaludin (Sultan Sepuh II)
9. P. Djaenudin Amir Sena I (Sultan Sepuh III)
10. P. Djaenudin Amir Sena II (Sultan Sepuh IV)
11. P. Sjafiudin/Sultan Matangadji (Sultan Sepuh
V)
12. P. Hasanuddin (Sultan Sepuh VI)
13. P. Djoharudin (Sultan Sepuh VII)
14. P. Radja Udaka (Sultan Sepuh VIII)
15. P. Radja Sulaeman (Sultan Sepuh IX)
16. P. Radja Atmadja (Sultan Sepuh X)
17. P. Radja Aluda Tajul Arifin (Sultan Sepuh XI)
18. P. Radja Radjaningrat (Sultan Sepuh XII)
19. P.R.A.DR.H. Maulana Pakuningrat. SH (Sultan
Sepuh XIII)
20. P.R.A Arief Natadiningrat. SE (Sultan Sepuh
XIV)
3. Pengertian dan Peranan Keraton Kesepuhan terhadap
pemeliharaan kebudayaan di Cirebon
Pada abad ke-15, pangeran Cakrabuana Putra Mahkota
Pajajaran membangun keraton yang kemudian diserahkan
kepada putrinya Ratu Ayu Pakungwati, Istri dari sunan
Gunung Jati, maka keratonnya di sebut Keraton
Pakungwati. Sejak didirikannya Keraton Kanoman pada
tahun 1679 oleh Sultan Anom I, Maka semenjak itu
Keraton Pakungwati bergelar Keraton Kesepuhan.
Keraton Kesepuhan adalah keraton termegah dan paling
terawat di Cirebon. Makna disetiap sudut Arsitektur
keraton ini pun terkenal paling bersejarah. Halaman
depan keraton ini dikelilingi tembok bata merah dan
terdapat pendopo didalamnya.
Keraton memiliki musium yang cukup lengkap dan
berisi benda pusaka dan lukisan koleksi kerajaan. Salah
satu koleksi yang di keramatkan yaitu Kereta Singa
Barong. Kereta Singa Barong saat ini tidak lagi
dipergunakan dan hanya dikeluarkan pada tiap 1 syawal
untuk di mandikan.
Bagian dalam keraton ini terdiri dari bangunan utama
yang berwarna putih, didalamnya terdapat ruang tamu,
ruang tidur dan singgasana raja.
Lokasi bangunan Keraton Kesepuhan membujur dari
utara ke selatan atau menghadap ke utara, karena
keraton-keraton di Jawa semuanya menghadap ke utara
artinya menghadap magnet dunia, arti falsafahnya sang
raja mengharapkan kekuatan.
Sebagai pusat dakwah Islam, keraton memegang peranan
yang sangat vital, ini jelas terlihat dari sejarah yang
menyebutkan bahwa Syaikh Syarif Hidayatullah (Sunan
Gunung Jati) selain berperan sebagai seorang sultan,
beliau juga adalah seorang hakim atau Qadi. Ajaran
agama Islam yang di bawa wali sanga ini memiliki
pemahaman bahwa Islam adalah agama yang Transformatif
yang bisa berakulturasi dengan budaya masyarakat di
wilayah penyebarannya masing-masing. Oleh karena itu
Keraton harus mampu menjadi ujung tombak dan juga pusat
dakwah ajaran Islam di wilayah kekuasaannya.
4. Arsitektur dan Interior
Apabila kita perhatikan ruang luar Keraton
Kesepuhan, kita bisa melihat bagaimana perpaduan unsur-
unsur Eropa seperti meriam dan Patung Singa dihalaman
muka, Furnitur dan meja kaca gaya Perancis tempat para
tamu sultan berkaca sebelum menghadap, gerbang ukiran
Bali dan Pintu Kayu model ukiran Perancis yang
menampakkan gambaran kosmopolitan Keraton Kesepuhan yan
tersimpan dalam musium Keraton.
Kegemaran Kesultanan Cirebon mengadopsi gaya dan
arsitektur model Eropa yang mengisi bagian dalam
Keraton Kesepuhan. Perhatikan bagaimana model dan
ukiran ruang pertemuan sultan dengan para menteri yang
di buat dengan model hampir sama dalam interior
kerajaan perancis dibawah dinasti Bourbon, seperti
model kursi, meja dan lampu gantung. Bagaimanapun
terdapat kombinasi gaya interior ini apabila kita
memperhatikan sembilan kain berwarna di latar belakang
singgasana raja yang melambangkan sosok wali sanga. Di
sini tradisi Jawa bercampur dengan Eropa yang telah 'di
lokalkan'.
Hal yang menarik dari Keraton Kesepuhan adalah
adanya piring-piring porselin asli Tiongkok yang
menjadi penghias dinding semua keraton di Cirebon. Tak
cuma di Keraton, Piring-piring porselin itu bertebaran
hampir di seluruh situs bersejarah di Cirebon.
5. Urutan-urutan Baluarti Keraton Kesepuhan Cirebon
Keraton Kesepuhan Cirebon mempunyai bangunan-
bangunan bersejarah dengan urutan Baluarti Keraton
meliputi:
1. Alun-alun
Semenjak zaman Sunan Gunung Jati, alun-alun depan
kraton dinamai Sangkala Buwana. Ditengah-tengahnya
tumbuh sepasang beringin jenggot, namun semenjak tahun
1930 M beringin itu sudah tidak ada lagi. Tanggal 6
November 1988 alun-alun diperindah disesuaikan dengan
pola keindahan tata kota oleh Pemda Kodya Cirebon
dengan seizin Sultan Sepuh Kasepuhan. Dahulu alun-alun
fungsinya untuk rapat akbar atau apel besar dan baris
berbaris para prajurit atau latihan perang-perangan
juga pentas perayaan negara.
2. Masjid Agung
Sebelah barat alun-alun berdiri bangunan masjid yang
dibangun pada tahun 1422 Saka atau 1500 M oleh Wali
Sanga dan masjid itu dinamai Sang Cipta Rasa. Sang=
Keagungan, Cipta=dibangun, Rasa=digunakan, artinya:
bangunan besar ini pergunakanlah untuk ibadah dan
kegiatan agama.
3. Panca Ratna
Sebelah selatan alun-alun atau sebelah barat jalan
menuju keraton berdiri bangunan tanpa dinding yang
dinamai Panca Ratna. Panca artinya lima, yang dimaksud
disini adalah hakekatnya Panca Indera atau gelaran yang
lima yaitu Pangucap, Pangirup (hidung), pangrungu
(telinga), pandeleng (mata), dan napsu. Panca juga
diartikan dengan “jalannya”, Ratna dengan “sengsem atau
suka”, maksudnya jalannya kesukaan.
Panca Ratna fungsinya untuk tempat Seba atau menghadap
para penggede desa atau kampong yang diterima oleh
Demang atau Wedana Keraton. Para penggede itu setiap
hari sabtu pertama diharuskan bermain “sodor berkuda”
yaitu semacam perang rider, permainan itu disebut
Sabton. Sultan sangat suka melihat permainan ini,
biasanya melihat dari Siti Inggil dengan para
pengiringnya.
4. Panca Niti
Sebelah timur jalan menuju Keraton terdapat bangunan
tanpa dinding yang dinamai Panca Niti. Panca=jalan, dan
Niti dari kata Nata atau Raja, namun yang dimaksud
disini adalah Atasan. Fungsinya :
a. Tempat perwira yang sedang melatih perang-
perangan prajurit,
b. Tempat istirahat setelah berbaris,
c. Tempat Jaksa yang akan menuntut hukuman mati
terdakwa kepada Hakim, dan pertimbangan apakah terdakwa
itu mendapat Grasi dari Raja,
d. Tempat petugas yang mengatur keramaian atau
pentasan yang diadakan Negara.
5. Kali Sipadu
Sebelah selatan Panca Ratna dan Panca Niti membentang
selokan dari barat ke timur yang dinamai Kali Sipadu
berfungsi sebagai pembatas antara masyarakat umum dan
penghuni baluarti Kraton Kasepuhan.
6. Kreteg Pangrawit
Diatas Kali Sipadu ada jembatan menuju Kraton yang
dinamai Kreteg Pangrawit. Kreteg artinya perasaan,
pangrawit berarti kecil namun maksudnya lembut/halus
atau baik. Artinya orang yang melintasi jembatan ini
diharapkan yang bermaksud baik-baik saja yang telah
diperiksa oleh kemitan Panca Ratna.
7. Lapangan Giyanti
Setelah melewati jembatan pangrawit sebelah barat jalan
terdapat lapangan yang dinamai Lapangan Giyanti,
dahulunya taman yang dibangun oleh Pangeran Arya Carbon
Kararangen (Pangeran Giyanti).
8. Siti Inggil
Sebelah timur lapangan Giyanti terdapat bangunan dari
bata merah berbentuk podium yang dinamai Siti Inggil.
Siti artinya tanah dan inggil=tinggi (dari bahasa
Cierebon). Siti Inggil dikelilingi tembok bata merah
berupa Candi Bentar. Candi=tumpukan, Bentar=bata. Tiap
pilar diatasnya terdapat Candi Laras. Candi=tumpukan,
Laras=sesuai. Artinya : Peraturan itu harus sesuai
dengan ketentuan hukum.
Pada Siti Inggil berdiri lima buah bangunan tanpa
dinding beratap sirap, deretan depan dari barat ketimur
yaitu :
a. Mande Pendawa Lima, bertiang lima menandakan
Rukun Islam. Fungsinya untuk duduk pengawal Raja.
b. Mande Malang Semirang atau Mande Jajar, tiang
tengahnya (yang berukir) enam buah melambangkan Rukun
Iman, seluruhnya terdapat 20 tiang, ini melambangkan
sifat yang 20 (sifat Ketuhanan). Malang Semirang
khususnya unutk tempat duduk Raja apabila melihat acara
di alun-alun dan juga apabila sedang mengadili
terdakwa.
c. Mande Semar Tinandu : bertiang dua
melambangkan Dua Kalimat Syahadat, fungsinya untuk
tempat duduk Penghulu atau Penasihat Raja.
d. Deretan belakang dari barat ke timur terdapat
Mande Karesmen yaitu Mande=bangunan, Karesmen=kesenian,
fungsinya untuk tempat membunyikan Gamelan Sekaten pada
tanggal 1 syawal dan 10 Dzulhijah waktunya ba’da shalat
‘id, jelasnya tempat membunyikan gamelan yang di anggap
sopan dan diperbolehkan oleh para Muthabiin di masa
lalu.
e. Mande Pengiring, fungsinya untuk tempat duduk
prajurit pengiring Raja, juga untuk tempat Hakim
menyidang terdakwa yang dituntut hukuman mati oleh
Jaksa.
Disebelah selatan Mande Pengiring terdapat dua buah
batu yang diberi nama ingga dan Yoni, melambangkan Adam
dan Hawa. Batu ini merupakan koleksi benda bersejarah.
Pada Siti Inggil, gapura depannya bergaya Bali yang
dinamakan Gapura Adi, gapura belakangnya dinamai Gapura
Banteng, karena di kaki gapura terdapat gambar banteng,
ini melambangkan kekuatan dan keberanian Aparatur
Negara.
Pada bangunan Siti Inggil terdapat pohon Tanjung yaitu
lambing Nanjung dalam bertahta, ada pepatah pawikon
yang berbunyi :
“Nanjung Ratu Waskitha Swalaning Paranala”
Artinya : “jadi Raja harus mengetahui penderitaan
rakyatnya.”
Di halaman depan Siti Inggil di tanam pohon sawo Kecik
(kecik=becik atau baik). Artinya diharapkan manusia itu
berkelakuan baik dan benar. Ada vakom sangkrit yang
berbunyi : “Satyam ewa jayatin” artinya kebenaran
adalah keunggulan.
Dihalaman Siti Inggil juga terdapat meja batu dari
Kalingga dan bangku batu dari Gujarat yang di bawa oleh
Dr. Raffles (orang Inggris yang tertarik pada sejarah
dunia) yang kemudian menyusun sejarah Indonesia.
Kemudian hasil penyusunannya diajarkan di sekolah-
sekolah masa colonial Belanda, kemudian ia menjadi
Gubernur Jenderal van Java tahun 1813-1818. Siti Inggil
engalami pemugaran oleh Dinas Held Keunde Belanda pada
tahun 1934-1938 namun tidak merubah bentuk aslinya.
9. Pengada
Sebelah selatan Siti Inggil terdapat bangunan tanpa
dinding menghadap ke barat yang dinamai Pengada atau
Kubeng artinya keliling (stelincup). Pengada fungsinya
untuk tempat Panca Lima. Panca diartikan
jalannya=gerakan, Lima yang di maksud adalah lima unsur
aparat yaitu Demang Dalem, Camat Dalem, Lurah Dalem,
Laskar Dalem dan Kaum Dalem. Tepatnya Pengada itu
tempat tugas kelima unsur aparat itu. Di depan Pengada
ditanami pohon Kepel. Kepel=genggam artinya lima orang
petugas saling menggenggam atau bersatu (bertanggung
jawab bersama dalam menjalankan tugas). Di depan
Pengada sebelah selatan ada pintu gerbang yang dinamai
Gerbang Pengada, dahulunya berdaun pintu seroja kayu
dan di jaga dua orang laskar bertombak. Sebelah timur
gerbang Pengada terdapat gerbang bentar, disana ada
penjaga lonceng maka gerbang itu disebut Gerbang
Lonceng, sekarang loncengnya sudah tidak ada lagi.
10. Kemandungan
Masuk gerbang Pengada kita akan sampai ke halaman yang
dinamai Kemandungan, dahulunya di dekat gerbang
Loncecng ada bangunan yang dinamai Gedung Kemandungan =
andalan (cagaran), gedung ini untuk penyimpanan senjata
atau alat perang, sebelah selatannya ada sumur yang
dinamai Sumur Kemandungan untuk mencuci senjata (alat
perang) pada setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 10
Muharram. Sekarang gedung Kemandungan sudah tidak ada
dan senjatanya dipindahkan ke gedung museum.
11. Langgar Agung
Sebelah barat Kemandungan berdiri bangunan yang dinamai
Langgar Agung atau Mushola untuk tempat shalat orang-
orang dalem, shalat terawih, shalat Idul Fitri dan Idul
Adha Sultan, kerabat dan Kaum Dalem. Didepan Langgar
Agung ada cungkup untuk tempat bedug, bedugnya dinamai
Sang Magiri yang artinya bila bedug di pukul sebagai
isyarat untuk memperingatkan masuknya waktu shalat agar
semuanya mengerjakan shalat. Ada hadist yang berbunyi :
“ajilu bishalati qoblal fawt wa ajilu qoblal mawt =
bershalatlah sebelum lewat waktunya dan bertaubatlah
sebelum mati.”
Langgar Agung sampai ekarang masih digunakan untuk
pelaksanaan selamatan bubur slabuk pada tanggal 10
Muharram, apem pada tanggal 15 Syafar, Mauludan pada
tanggal 12 Rabiul Awwal (ba’da Shalat Isya sampai
selesai), ta’jilan pada bulan Ramadhan, selamatan
lebaran pada tanggal 1 Syawal dan penyembelihan Qurban
pada tanggal 8 Dzulhijjah (‘Idul Adha) oleh pihak
Keraton.
12. Pintu Gledegan
Dari Kemandungan arah ke selatan melalui gerbang yang
dinamai pintu Gledegan sekarang berdaun pintu teralis
dari besi, dahulu di jaga dua orang Laskar/prajurit
bertomba. Bila ada orang yang akan masuk maka akan
diperiksa dengan suara menggelegar/menggeledeg seperti
petir. Oleh sebab itu gerbang ini dinamai Pintu
Gledegan.
13. Taman Bunderan Dewan daru
Setelah melewati pintu Gledegan kita akan menemui
sebuah taman yang dinamai Taman Bunderan Dewan Daru.
Taman ini dibuat Plan soen rolaknya dari batu cadas, di
taman ini terdapat 8 buah pohon Dewan Daru. Oleh karena
itu, dinamai Taman Bunderan Dewan Daru (bentuknya
bundar). Maknanya adalah bunderan berarti sepakat,
dewan=dewa atau makhluk halus, Daru=cahaya, artinya:
jadilah orang yang menerangi sesama mereka yang hidup
dalam rasa kegelapan.
Ditaman ini terdapat yaitu:
a. Nandi (patung lembu kecil) = lambang
kepercayaan Hindu sebagai koleksi.
b. Pohon Soka sebagai lambang suka (hidup bersuka
hati).
c. Patung 2 ekor Macan Putih merupakan lambang
Padjajaran.
d. Meja dan bangku batu sama dengan yang ada di
halaman depan Siti Inggil.
e. Dua buah meriam persembahan dari Prabu
Kabunangka Pakuan, meriam ini dinamai Ki Santoma dan
Nyi Santomi.
14. Museum Benda Kuno
Sebelah barat Taman Bunderan Dewan daru berdiri
bangunan museum yang pernah di pugar oleh departemen P
& K Dinas Purbakala pada tahun 1974-1975 M, dan
bentuknya berubah menjadi bentuk huruf E tapi tembok
tengahnya (yang bagian atas pilarnya terdapat memolo
bunga teratai kudup) masih asli. Pintu musim bagian
tengah khusus untuk masuk “Orang Dinas” yang
berkepentingan saja, sementara untuk pengunjung wisata
masuk dari pintu sebelah selatan dan keluar dari pintu
sebelah utara.
Museum ini digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-
barang antik peninggalan sejarah seperti barang
kerajinan dari dalam dan luar negeri, alat upacara
adat, dan juga senjata sebagai koleksi diantaranya :
a. Seperangkat gamelan degung persembahan dari Ki
Gede Kawungcaang Banten tahun 1426 M karena puterinya
Dewi Kawung Anten dinikahi Sunan Gunung Jati. Degung
ini merupakan duplikat dari degung pusaka Padjajaran.
b. Seperangkat gamelan berlaras slendro dan wayang
Purwa dari Cirebon tahun 1748 M yang merupakan
peninggalan Sultan Sepuh IV, gamelan ini dinamai Si
Ketuyung.
c. Vitrin I : berisi Pagoda Graken untuk tempat
jamu, peti Kandaga dari Suasa untuk tempat perhiasan,
dan kaca rias (cermin). Semuanya peninggalan tahun 1506
M.
d. Empat buah rebana peninggalan Sunan Kalijaga
tahun 1412 M dan Genta (bel) yang dinamai Bergawang,
dahulu sebagai tanda pelantikan Sunan Gunung Jati atau
Syekh Syarif Hidayatullah sebagai Sultan Auliya Negara
Cirebon oleh Dewan Wali Sanga, yang menguasai daerah
Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majalengka pada tahun
1429 M.
e. Seperangkat gamelan Sekaten persembahan dari
Sultan Demak III (Sultan Trenggono) pada waktu
pernikahan Ratu Mas Nyawa (adik Sultan Trenggono)
dengan Pangeran Bratakelana putera Sunan Gunung Jati
tahun 1495 M. gamelan ini digunakan sebagai alat
propaganda untuk memikat orang-orang Hindu masuk Islam,
hingga sekarang gamelan Sekaten ini dibunyikan setiap
hari raya ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha di Siti Inggil.
f. Vitrin II: berisi tempat tinta dari Cina tahun
1967 M, Ani-ani untuk potong padi, gelas minum dari VOC
tahun 1745 M. alat upacara Raja yaitu dua buah
jantungan, dua buah Manggaran, dan dua buah Nagan
terbuat dari perak (sekarang digunakan untuk upacara
Gerebeg Mulud), standar lilin Kristal dari Perancis
tahun 1738 M, lumbung padi (miniature) terbuat dari
uang kepeng Cina, empat buah kerang buntet dari Laut
Banda, ukiran kayu berbentuk naga badannya saling
melilit disebut Naga Tunggul Wulung, menurut
kepercayaan dulu sebagai tumbal (mascot), Naga Tunggul
Wulung itu pengawalnya 3 Pohaci (Dewi Padi), satu set
perhiasan pengantin untuk putera Raja tahun 1526 M
terbuat dari logam kuningan sari, dan lain-lain.
g. Vitrin III: berisi 24 buah baju logam disebut
Harnas/Malin juga disebut baju Kere dari Portugis tahun
1527 M.
h. Tiga buah peti kayu berukir dari Cina dean 6
buah peti dari Mesir pada zaman Sunan Gunung Jati.
i. Vitrin IV : berisi Kujang, Cundrik Pedang,
dan Trisula.
j. Vitrin V : berisi beberapa buah mata tombak.
k. Vitrin VI : berisi bedil berlidi (penyocok
mesiu) dari Mesir, bedil dobel Loop, dan pedang dari
Portugis.
l. Diruang pintu tengah terdapat dua buah meriam
dari Kalingga India persembahan dari Patih Keling yang
di-Islam-kan oleh Sunan Gunung Jati tahun 1423 M,
kemudian Ki patih beserta anak buahnya turun temurun
mengabdi untuk menjaga makam Sunan Gunung Jati hingga
sekarang.
m. Vitrin VII : berisi barang keramik dari Cina
tahun 1424 M, dibawahnya berisi senjata/keris-keris
persembahan dari masyarakat.
n. Vitrin VIII : berisi beberapa buah Genta
kerajinan cina, beberapa buah kendi terbuat dari buah
labu, 4 buah patung kayu dari Bali yang disebut Krisna
Murti. Krisna=Wisnu, Murti=kuasa, ini menggambarkan
Dewa Wisnu dilahirkan ke dunia untuk mencegah kemurkaan
manusia, jin, dan hewan. Beberapa buah piring dan
mangkuk persembahan dari Sultan Aryadilah Palembang,
kelapa Janggi penemuan Pangeran Cakrabuwana dari Laut
Aden sewaktu pulang dari Haji tahun 1390 M, dan lain-
lain.
o. Rak berisi beberapa buah tombak seligi.
p. Ditembok sebelah barat terdapat panah beserta
gendewanya, disampingnya rak berisi beberapa buah
tombak.
q. Vitrin IX : berisi Kujang dan Cundrik dari
Padjajaran sejak zaman Pangeran Cakra Buwana lalu
diberikan kepada Sunan Gunung Jati.
r. Beberapa buah meriam dari Cina tahun 1676 M
dan meriam dari Portugis tahun 1527 M. pada waktu itu
portugis memonopoli perdagangan di Sunda Kelapa dan
menduduki Sunda Kelapa kemudian di usir oleh Tubagus
Paseh (Fatahillah) menantu Sunan Gunung Jati dengan
bantuan sisa Laskar Pajang, kemudian Portugis mundur ke
Sumatera dan akhirnya ke Malaka, diantara meriam dari
Cina dan Portugis terdapat alat debus dari Banten
persembahan Sultan Hasanudin Banten tahun 1552 M untuk
Panembahan Pakung Wati, dibawahnya terdapat batu peluru
bandil (bahasa Arab disebut Hajar Rajam) unutk perang
pada masa dulu.
s. Rak berisi beberapa buah tombak Cis untuk
khotbah.
t. Vitrin X : berisi 48 buah tombak dwisula, 37
buah Trisula, 40 buah Catur Sula, yang kesemuanya di
buat oleh Sultan Sepuh V mandainya (dibuat) di Desa
Malanghaji tahun 1776 M, beberapa buah peninggalan
kompeni Belanda tahun 1745 M dan senjata-senjata
persembahan dari masyarakat untuk dimusiumkan.
u. Di sudut ruangan terdapat satu set meja kursi
hitam model Eropa tahun 1845 M, disampingnya terdapat
ukiran kayu motif Wadasan ditumbuhi pohon teratai dari
Cina persembahan kapten Cina dari Pekalongan yang
bernama Tan Tjoeng Lay yang ahli bahasa Belanda,
Inggris, Tak Tje, Melayu, Jawa, dan Sunda juga suka
dengan ilmu Kejawen. Kemudian masuk Islam dam mengabdi
pada Sultan Sepuh I, di beri gelar Tumenggung Ariya
Wira Cula tahun 1676-1697 M.
v. Vitrin XI : berisi beberapa mata tombak zaman
Sultan Sepuh V.
w. Vitrin XII : berisi Pagoda Graken, mangkok besar
dan Kendi Keramik dari Mongolia dinasti Ming, dan
cangkir dari Cina tahun 1424 M.
x. Meja Vitrin I : berisi mata tombak ditatrap
emas, keris Sekin karya empu zaman Sunan Gunung Jati,
mata tombak besar tatrap emas khusus untuk Ki Bergawa
perwira kuat berbadan besar seperti Samson atau
Hercules dan Badik dari Makasar.
y. Meja Vitrin II : berisi busana putera-puteri
Sultan masa Sultan Sepuh X.
z. Vitrin XII : berisi mata tombak dan keris.
aa. Di pojok sebelah timur terdapat ukiran kayu
Ganesha naik gajah karya Panembahan Girilaya tahun 1582
M.
bb. Seperangkat alat Tedak Siti Mudun Lemah (Turun
Tanah) terdiri atas : 1 buah sangkar bamboo, 1 buah
kursi dan tangga kecil berundaga lima untuk upacara
turun tanah anak umur tujuh bulan, acaranya setelah
undangan kumpul, Si Anak di papah lalu kakinya
diinjakkan pada ambalan tangga dan terakhir dimasukkan
sangkar yang didalamnya ada tanah kemudian kakinya
diinjakkan ke tanah. Kemudian di suruh memilih. Jika
mengambil padi maka berbakat menjadi petani, jika uang
maka pedagang, pensil jadi pegawai, buku maka jadi ahli
ilmu, Qur’an ahli Agama, emas banyak harta, pisau jadi
tentara. Peralatan ini peninggalan Sultan Sepuh XI
tahun 1899 M.
cc. Di sekeliling tembok musium terdapat beberapa
buah ukiran kayu diantaranya ukiran kayu Mantingan yang
menggambarkan manusia purba dari Desa Mantingan,
Kerajaan Pajang pada zaman Panembahan Pakung Wati I
yang bersahabat dengan Sultan Pajang dan berjodoh
dengan puteri Pajang, Ratu Mas Gulampok Angroros tahun
1510 M, ukiran kayu menggambarkan dua makhluk prabangsa
berhadap-hadapan karya Panembahan Pakung Wati I dikala
melihat awan bergumpal di langit berbentuk binatang
lalu di gambar di tanah kemudian di buatlah ukirannya.
15. Musium Kereta
Sebelah timur Taman Bunderan Dewan Daru berdiri
bangunan yang berfungsi untuk tempat penyimpanan kereta
pusaka yang dinamai Kereta Singa Barong. Singa dari
Sing Ngarani (bahasa Cirebon), Barong dari bareng-
bareng. Jadi Singa Barong itu artinya Sing ngarani
bareng-bareng, arti bahasa Indonesianya yang memberi
nama bersama-sama.
Kereta ini dibuat tahun 1549 M atas prakarsa Panembahan
Pakung Wati I mengambil pola makhluk prabangsa.
arsiteknya Panembahan Losari, Werk Bas Dalem Gebang
Sepuh dan pemahatnya Ki Nataguna dari Kaliwulu. Kereta
Singa Barong perwujudan dari tiga binatang jadi satu
yaitu : 1). Belalai gajah melambangkan persahabatan
dengan India yang beragama Hindu; 2). Kepala Naga
melambangkan persahabatan dengan Cina yang beragama
Budha; 3). sayap dan badan mengambil dari Buraq
melambangkan persahabatan dengan Mesir yang beragama
Islam. Ketiga kebudayaan tersebut menjadi satu
(Hindu,Budha,Islam) digambarkan dengan Tri Sula di
belalai. Tri=tiga, Sula=tajam, yang di maksud adalah
“tajamnya alam pikiran manusia yaitu Cipta, Karsa, dan
Rasa. Ada sastra Jawa yang berbunyi “Witing guna saka
kaweruh dayane satuhu” yang artinya adalah asalnya
kebijaksanaan itu dari pengetahuan jalankanlah dengan
mantap dan baik.
kereta ini dahulunya digunakan untuk Upacara Kirab
Keliling Kota Cirebon setiap tanggal 1 sura atau
Muharram dengan di tarik oleh 4 ekor kerbau bule.
semenjak tahun 1942 M sudah tidak dipakai lagi. Didalam
musium kereta juga terdapat 2 buah Tandu Jempana dari
Cina persembahan dari Kapten Tan Tjoeng Lay dan Kapten
Tan Boen Wee tahun 1676 M. Tandu Jempana ini untuk
permaisuri dan putera mahkota.
Tandu Garuda Mina dibuat tahun 1777 di Gempol
Palimanan, tandu ini dipergunakan untuk mengarak anak
yang mau khitan. Dimusium juga terdapat pedang-pedang
dari Portugis dan Belanda, 2 buah meriam dari Mongolia
tahun 1424 M yang berbentuk naga. Di belakang kereta
terdapat tombak-tombak panjang berbendera kuning yang
disebut Blandrang, biasanya tombak-tombak ini dibawa
oleh Prajurit Panyutran sebagai barisan kehormatan,
juga terdapat Tunggul Gada/Tunggul Manik sebagai
lambing penerangan, dan Payung Keropak sebagai lambing
pengayoman. Dimusium juga terdapat seperangkat Angklung
kuno persembahn dari masyarakat daerah Kuningan.
16. Tugu Manunggal
Sebelah selatan Taman Bunderan Dewan Daru terdapat batu
pendek di kelilingi 8 buah pot bunga, maksudnya lambing
kepercayaan Islam menyembah kepada Allah yang satu dzat
sifatnya . Tugu ini dinamai Tugu Manunggal.
17. Lunjuk
Sebelah barat Tugu Manunggal berdiri bangunan yang
disebut Lunjuk yang artinya petunjuk. Fungsinya untuk
tempat staf harian yang tugasnya melayani tamu yang mau
menghadap Raja (mencatat dan melaporkan).
18. Sri Manganti
Sebelah timur Tugu Manunggal berdiri bangunan tanpa
dinding yang disebut Sri Manganti. Sri = Raja, Manganti
= menunggu. Artinya : tempat menunggu keputusan Raja
setelah melapor di Lunjuk.
19. Kuncung dan Kutagara Wadasan
Sebelah selatan Tugu Manunggal terdapat bangunan
beratap sirap disebut Kuncung (poni) fungsinya untuk
tempat parkir kendaraan Raja/Sultan, dibangun tahun
1678 M oleh Sultan Sepuh I. Kuncung bergebang putih
dibuat mengandung seni khas Cirebon, bawahnya berukir
Wadasan yang melambangkan “manusia hidup harus
mempunyai pondasi yang kuat”, atasnya berukir Mega
Mendungan yang melambangkan ‘jika sudah menjadi
pemimpin atau Raja harus dapat mengayomi bawahannya
atau rakyatnya.Gapura ini disebut Kutagara Wadasan.
20. Jinem Pangrawit
Sebelah selatan Kuncung terdapat ruangan sebagai
serambi depan keraton yang disebut Jinem Pangrawit.
Jinem = Kejineman (tempat tugas), Pangrawit dari kata
rawit (kecil) yang di maksud halus atau bagus (baik),
fungsinya untuk tempat tugas Pangeran Patih atau Wakil
Sultan menerima tamu.
21. Pintu Buk Bacem
Sebelah barat dan timur Jinem Pangrawit terdapat pintu
gerbang beratap tembok lengkung (hoeg/buk) berdaun
pintu kayu. Kayunya di bacem dulu (direndam dengan di
beri ramuan) sehingga disebut Pintu Buk Bacem. Pintu
yang di sebelah barat untuk pengunjung wisata, dan yang
sebelah timur untuk keluar-masuk penghuni Keraton tiap
hari.
22. Gajah Nguling
Sebelah dalam Jinem Pangrawit terdapat bangunan tanpa
dinding bertiang putih disebut Loos Gajah Nguling
mengambil dari gajah sedang nguling (menguak)
belalainya bengkok, bentuk bangunan ini pun tidak lurus
seperti belalai gajah sedang menguak. Maksudnya tidak
boleh boros harus irit. Loos ini dibangun oleh Sultan
Sepuh IX tahun 1845 M, fungsinya sebagai penghubung
Jinem Pangrawit dengan Bangsal Pringgandani.
23. Bangsal Pringgandani
Sebelah dalam atau selatan Loos Gajah Nguling terdapat
ruangan yang dinamai Bangsal Pringgandani mengambil
nama dari cerita pewayangan, fungsinya untuk pisowan
(menghadap) para Bupati Cirebon, Kuningan, Indramayu,
Majalengka, dan digunakan juga sebagai tempat sidang
para warga Keraton.
24. Langgar Alit
Sebelah barat Bangsal Pringgandani berdiri bangunan
tanpa dinding yang dinamai Langgar Alit. Fungsinya
untuk tempat tadarus setelah shalat Tarawih kemudian
membunyikan Terbang/Gembyung pada tanggal 15 Ramadhan
diadakan selamatan khatam Qur’an ke I, tanggal 17
Ramadhan peringatan Nuzulul Qur’an, tanggal 29 Ramadhan
Maleman, tanggal 30 Ramadhan khatam ke II, tanggal 1
Syawal ba’da Isya penghulu dan kaum menerima zakat
Fitrah dari Sultan Sepuh sekeluarga, tanggal 27 rajab
ba’da Isya diadakan ‘Isra Mi’raj (rajaban), tanggal 15
sya’ban diadakan Nisfu Sya’ban (Rewahan), dan
peringatan hari-hari besar Islam hingga sekarang.
Langgar Alit pernah di pugar bersamaan dengan Siti
Inggil, dan lantainya diganti dengan marmer. Sebelah
utara Langgar Alit sejajar tembok terdapat pintu yang
disebut Pintu Putri. Pintu ini menuju ke Kaputren, umum
tidak boleh melalui pintu ini.
25. Jinem Arum
Sebelah timur Bangsal Pringgandani berdiri bangunan
tanpa dinding dinamai Jinem Arum yang fungsinya untuk
ruang tunggu wargi yang mau menghadap Sultan.
26. Kaputran
Sebelah timur Jinem Arum berdiri bangunan menghadap ke
utara yang dinamai Kaputren, fungsinya untuk tempat
tinggal putera Sultan yang laki-laki.
27. Bangsal Prabayaksa
Sebelah dalam Bangsal Pringgandani terdapat ruangan
yang disebut Bangsal Prabayaksa. Praba = sayap, Yaksa =
besar, maksudnya “Sultan melindungi rakyat dengan kedua
tangannya yang besar seperti induk ayam melindungi
anaknya dengan kedua sayapnya.” Yang dimaksud berarti
Besar kekuasaannya. Bangsal Prabayaksa dibangun tahun
1682 oleh Sultan Sepuh I, dan fungsinya untuk tempat
siding para menteri Negara Keraton Kasepuhan. Di
Bangsal Prabayaksa terdapat meja/kursi bercat kuning
gading dibuat tahun 1738 M, juga lampu kristal dari
Perancis tahun 1738, dan lampu storlop prasman dari VOC
taun 1745, ditembok bangsal terpasang tegel-tegel
proselen berwarna biru dan cokelat dari VOC, tegel
cokelat gambarnya mengandung cerita dari Injil juga
piring-piring keramik dari Cina dinasti Han Boe Tjie
tahun 1424 M, tiga buah lukisan dari Belanda, dan satu
buah dari Jerman tahun 1745 M.
Ditembok Bangsal Prabayaksa terdapat empat buah relief
karya Pangeran Arya Carbon Kararangen tahun 1710 (adik
Sultan Sepuh II). Relief ini dinamai Kembang Kanigaran
artinya Lambang kenegaraan yang dimaksud adalah Sri
Sultan dalam memegang tampuk kenegaraan harus welas
asih pada rakyatnya.
28. Kaputren
Sebelah barat relief terdapat pintu menuju bangunan
yang dinamai Kaputren yang fungsinya untuk tempat
tinggal puteri sultan.
29. Dalem Arum
Sebelah timur relief terdapat pintu menuju ruangan yang
disebut Dalem Arum atau Kedaton yang fungsinya untuk
tempat tinggal Sultan dan keluarganya turun temurun
hingga sekarang, umum dilarang masuk.
30. Bangsal Agung Panembahan
Sebelah selatan Bangsal Prabayaksa naik tangga terdapat
ruangan yang disebut Bangsal Agung Panembahan.
Fungsinya untuk tempat singgasana Gusti Panembahan.
Didalam Bangsal Agung Panembahan terdapat kursi
Singgasana dengan mejanya berkaki gambar ular yang
melambangkan dahulu ucapan Raja merupakan hokum,
dibelakang singgasana terdapat tempat tidur yang
disebut Ranjang Kencana untuk istirahat siang
Raja/Sultan. Sebelah kanan dan kiri singgasana terdapat
meja dan kursi untuk permaisuri dan putera Mahkota bila
berkenan hadir.
Sekarang Bangsal Panembahan dipergunakan untuk sesaji
sarana Panjang Jimat (selamatan Maulud) yang
mengerjakan kaum Masjid Agung dan disaksikan oleh
Sultan, Raden Ayu, dan kerabat keraton, waktunya ba’da
Isya tanggal 12 Rabiul Awwal, setelah selesai kemudian
diiring menuju Langgar Agung.
Lantai Bangsal Agung Panembahan masih asli tahun 1529,
sedangkan lantai Bangsal Prabayaksa dan Pringgandani
sudah diganti tahun 1934, dan Jinem Pangrawit tahun
1997.
31. Pungkuran
Sebelah selatan Bangsal Agung Panembahan terdapat
ruangan tanpa dinding merupakan Serambi belakan yang
disebut Pungkuran atau Buritan karena letaknya paling
belakang. Fungsinya untuk tempat sesaji sarana maulid
Nabi Muhammad SAW.
32. Dapur Mulud
Didepan Kaputren agak ke barat berdiri bangunan
menghadap ke timur yang dinamai Dapur Mulud yang
fungsinya untuk tempat memasak selamatan Maulid Nabi,
yang memasaknya ibu-ibu Kaum Masjid Agung.
33. Pamburatan
Sebelah selatan Kaputren terdapat bangunan yang dinamai
Pamburatan (Pengguratan) untuk tempat menggurat
(ngerik) kayu-kayu wangi bahan boreh (param) pelengkap
selamatan Maulid Nabi SAW.
6. Tadisi yang ada dalam Keraton Kasepuhan Cirebon
a. Syawalan Gunung Jati
Setiap awal bula syawal masyarakat wilayah Cirebon
umumnya melakukan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Di
samping itu juga untuk melakukan tahlilan.
b. Ganti Welit
Upacara yag dilaksanakan setiap tahun di Makam
Kramat Trusmi untuk mengganti atap makam keluarga Ki
Buyut Trusmi yang menggunakan Welit (anyaman daun
kelapa). Upacara dilakukan oleh masyarakat Trusmi.
Biasanya dilaksanakan pada tanggal 25 bulan Mulud.
c. Rajaban
Upacara dan ziarah ke makam Pangeran Panjunan dan
Pangeran Kejaksan di Plangon. Umumnya dihadiri oleh
para kerabat dari keturunan dari kedua Pangeran
tersebut. Dilaksanakan setiap 27 Rajab. Terletak di
obyek wisata Plangon Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber
kurang lebih 1 Km dari pusat kota Sumber.
d. Ganti Sirap
Upacara yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali di
makam kramat Ki Buyut Trusmi untuk mengganti atap makam
yang menggunakan Sirap. Biasanya dimeriahkan dengan
pertunjukan wayang Kulit dan Terbang.
e. Muludan
Upacara adat yang dilaksanakan setiap bulan Mulud
(Maulud) di Makam Sunan Gunung Jati. Yaitu kegiatan
membersihkan / mencuci Pusaka Keraton yang dikenal
dengan istilah Panjang Jimat. Kegiatan ini dilaksanakan
pada tanggal 8 s/d 12 Mulud. Sedangkan pusat kegiatan
dilaksanakan di Keraton.
Upacara Maulid Nabi dilakukan setelah beliau wafat,±
700 tahun setelah beliau wafat (P.S. Sulendraningrat,
1978:85) upacara ini dilakukan sebagai rasa hormat dan
sebagai peringatan hari kelahiran kepada junjungan
besar Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, kata maulud
berasal dari bahasa Arab “Maulid” yang memiliki sebuah
arti kelahiran. Upacara Maulid Nabi di Cirebon telah
dilakkan sejak abad ke 15, sejak pemerintahan Sunan
Gunung Jati upacara ini dilakukan dengan besar-besaran.
Berbeda dengan masa pemerintahan Pangeran Cakrabuana
yang hanya dilakukan dengan cara sederhana. Upacara
Maulid Nabi di kraton Cirebon diadakan setiap tahun
hingga sekarang yang oleh masyarakat Cirebon bisebut
sebagai upacara “IRING-IRINGAN PANJANG JIMAT” (P.S.
Sulendraningrat, 1978:86).
f. Salawean Trusmi
Salah satu kegiatan ziarah yang dilaksanakan di
Makam Ki Buyut Trusmi. Di samping itu juga dilaksanakan
tahlilan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tanggal 25
bulan Mulud.
g. Nadran
Nadran atau pesta laut seperti umumnya dilaksanakan
oleh nelayan dengan tujuan untuk keselamatan dan
upacara terima kasih kepada Sang Pencipta yang telah
memberikan rezeki. Dilaksanakan dihampir sepanjang
pantai (tempat berlabuh nelayan) dengan waktu kegiatan
bervariasi.
h. Upacara Pajang Jimat
Salah satu upacara yang dilakukan di Kerajaan
Cirebon adalah Upacara Pajang Jimat. Pajang Jimat
memiliki beberapa pengertian, Pajang yang berarti terus
menerus diadakan, yakni setiap tahun, dan Jimat yang
berarti, dipuja-puja (dipundi-pundi/dipusti-pusti) di
dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW
(P.S. Sulendraningrat, 1978:87). Pajang Jimat merupakn
sebuah piring besar (berbentuk elips) yang terbuat dari
kuningan. Bagi Cirebon Pajang Jimat memiliki sejarah
khusus, yakni benda pusaka Kraton Cirebon, yang
merupakan pemberian Hyang Bango kepada Pangeran
Cakrabuana ketika mencari agama Nabi (Islam).
Upacara Pajang Jimat pada Kraton Cirebon dilakukan
pada tanggal 12 Rabiul Awal, setelah Isya’, upacara
penurunan Pajang Jimat dilakukan oleh petugas dan ahli
agama di lingkungan kraton. Turunnya Pajang Jimat
dimulai dari ruang Kaputren naik ke Prabayaksa dam
selanjutnya diterima oleh petugas khusus yang telah
diatur. Adapun tatacara dan atribut dalam upacara
Pajang Jimat, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Beberapa lilin dipasang diatas standarnya.
2. Dua buah manggaran, dan buah nagan da dua buah
jantungan.
3. Kembang goyak (kembang bentuuk sumping) 4 kaki.
4. Serbad dua guci dan duapuluh botl bir tengahan.
5. Boreh/parem.
6. Tumpeng.
7. Ancak sangar (panggung) 4 buah yang keluar dari
pintu Pringgadani.
8. 4 buah dongdang yang berisi makanan, menyusul
belakangan, keluar dari pintu barat Bangsal
Pringgandani, ke teras Jinem.
Upacara irig-iringan Pajang Jimat di Kraton Kasepuhan
Cirebon ini sebagai gambaran peranan seorang dukun bayi
(bidan). Jam 24.00 Pajang Jimat kembali dari Langgar
Keraton masukke Kraton dengan melalui pintu sebelah
barat menuju Kaputren, maka berakhirlah acara Upacara
Maulid Nabi (P.S. sulendraningrat, 1978:87-94).
PENUTUP
Mengunjungi Keraton Kasepuhan seakan-akan
mengunjungi Kota Cirebon tempo dulu. Keberadaan Keraton
Kasepuhan juga kian mengukuhkan bahwa di kota Cirebon
pernah terjadi akulturasi. Akulturasi yang terjadi
tidak saja antara kebudayaan Jawa dengan kebudayaan
Sunda, tapi juga dengan berbagai kebudayaan di dunia,
seperti Cina,India, Arab, dan Eropa. Hal inilah yang
membentuk identitas dan tipikal masyarakat Cirebon
dewasa ini, yang bukan Jawa dan bukan Sunda. Kesan
tersebut sudah terasa sedari awal memasuki lokasi
keraton. Keberadaan dua patung macan putih di
gerbangnya, selain melambangkan bahwa Kesultanan
Cirebon merupakan penerus Kerajaan Padjajaran, juga
memperlihatkan pengaruh agama Hindu sebagai agama resmi
Kerajaan Padjajaran. Gerbangnya yang menyerupai pura di
Bali, ukiran daun pintu gapuranya yang bergaya Eropa,
pagar Siti Hingilnya dari keramik Cina, dan tembok yang
mengelilingi keraton terbuat dari bata merah khas
arsitektur Jawa, merupakan bukti lain terjadinya
akulturasi.
Nuansa akulturasi kian kentara ketika memasuki
ruang depannya yang berfungsi sebagai museum. Selain
berisi berbagai pernak-pernik khas kerajaan Jawa pada
umumnya, seperti kereta kencana singa barong, dua tandu
kuno, dan berbagai jenis senjata pusaka berusia ratusan
tahun, di museum ini pengunjung juga dapat melihat
berbagai koleksi cinderamata berupa perhiasan dan
senjata dari luar negeri, seperti senapan Mesir, meriam
Mongol, dan zirah Portugis. Singgasana raja yang
terbuat dari kayu sederhana dengan latar sembilan warna
bendera yang melambangkan Wali Songo. Hal ini
membuktikan bahwa Kesultanan Cirebon juga terpengaruh
oleh budaya Jawa dan agama Islam. Selain itu, di
halaman belakang pengunjung dapat melihat taman istana
dan beberapa sumur dari mata air yang dianggap keramat
dan membawa berkah. Kawasan ini ramai dikunjungi
peziarah pada upacara panjang jimat yang digelar pihak
keraton setiap tahun untuk memperingati Maulid Nabi
Muhammad SAW .
DAFTAR PUSTAKA
http://edywitanto.wordpress.com/sejarah-perkembangan-
pemikiran-dan-peradaban-islam/sejarah-masuknya-islam-ke-
indonesia/islam-di-kerajaan-cirebon/
http://cerelyafarah.wordpress.com/2013/04/17/kerajaan-
cirebon/
http://rizkidinda.blogspot.com/
http://id.w ikipedia.org/wiki/Keraton_Kasepuhan
http://indahcahayaa.blogspot.com/