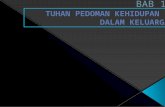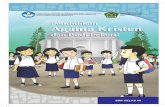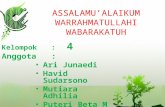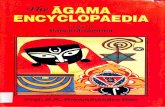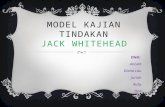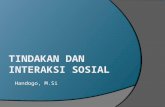Agama Sebagai Motivator Tindakan Sosial
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Agama Sebagai Motivator Tindakan Sosial
UAGAMA SEBAGAI MOTIVATOR TINDAKAN SOSIAL
Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
“Sosiologi Agama”
Dosen Pengampu: Faiz Tajul Millah, MA
Disusun Oleh:
Masduki Zakariya
NIM: 11.01.0026
Nurhayati
NIM: 12.01.0027
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA
KUTAI TIMUR
2015
Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan pembuatan tugas makalah mata
kuliah Pengembangan Kurikulum PAI. Shalawat serta salam, tetap
tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad Saw. yang telah
membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman Islamiyah.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Faiz Tajul Millah,
MA selaku dosen pembimbing mata kuliah Sosiologi Agama. Karena atas
bimbingan dan segala dukungan yang telah beliau berikan pada penulis,
penulis mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan beliau. Tidak
lupa penulis mengucapkan terima kasih pula kepada teman-teman yang
selalu ikut berpartisipasi memberikan kritik dan saran yang membangun
terhadap karyatulis penulis.
Kutai Timur, April 2015
Penulis
ii
Daftar Isi
Kata Pengantar .................................................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................. 2
C. Tujuan Penulisan................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN .................................................................................... 3
A. Pengertian Agama ................................................................................. 3
1. Agama Sebagai Fakta Sosial ............................................................. 3
2. Agama dan Religi .............................................................................. 4
B. Agama Dalam Relasi Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan ............ 7
C. Agama Sebagai Motivator Tindakan Sosial ......................................... 9
BAB III PENUTUP ..................................................................................... 16
A. Simpulan ............................................................................................. 16
B. Saran ................................................................................................... 17
DAFTAR PUSTAKA
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Agama telah hadir sebagai fakta sosial. Meskipun secara empiris,
memelajari ilmu sosial untuk bidang keagamaan tidak untuk membenarkan
objek kajian itu sendiri. Karena pada dasarnya, agama ada dibutuhkan untuk
mendorong perkembangan umat manusia —pemeluknya— menuju
kebahagiaan, kemuliaan, dan kemudahan. Yang pertamakali adalah aspek
spiritual, atau yang lebih mendekati secara saintifik adalah dorongan psikologis.
Harus diakui, sedikit demi sedikit ada perbedaan perspektif dalam
memandang agama dari awal perkembangan ilmu sosial atau pun psikologi
pada akhir 1800-an hingga awal 1900-an sampai dewasa ini. Kini, agama tidak
semata objek kajian. Akan tetapi telah disadari bahwa aspek nilai yang
dikandungnya bermanfaat dalam pengembangan masyarakat di bagian mana
pun di dunia. Oleh karena itu, mengamati bagaimana agama dapat mendorong
timbulnya tindakan sosial adalah hal yang menarik bagi sosiologi, sosiologi
agama.
Tentunya, fakta yang dihadirkan bukanlah hal yang dipilih untuk
dinyatakan benar menurut agama itu. Karena perbedaan keyakinan,
pemahaman, dan sikap toleransi harus diakui juga di belahan mana pun di bumi
terjadi gesekan satu sama lain bahkan oleh sekte atau aliran di dalam agama itu
sendiri. Hal ini juga sasaran yang patut dikaji dari agama sebagai motivator
tindakan sosial. Namun, sudah menjadi tugas ilmu pengetahuan untuk mengkaji
kemudian mengembangkan kea rah yang lebih baik.
Dalam latar belakangnya, agama —haruslah— menuntun manusia ke
kehidupan yang lebih baik secara kolektif menurut idealisme keyakinannya.
Karena kehidupan manusia tidak dapat hanya dikaitkan dengan kehidupan
individual semata, maka agama merupakan gerakan keyakinan yang sama yang
dianut oleh penganutnya. Tindakan sosial positif dapat dilakukan penganut
2
agama terhadap kalangannya. Namun tindakan sosial lain dapat terjadi terhadap
penganut agama lain yang mengarah pada tindakan negatif bahkan nihilisme.
Oleh karena itu, makalah ini menyajikan susunan asal-muasal tindakan
sosial yang dilatarbelakangi oleh keyakinan beragama. Agama begitu penting
bagi aspek sosial, tapi juga begitu genting jika terdapat kesalahpahaman atau
kekurangtoleransian. Makalah ini disusun dengan judul Agama Sebagai
Motivator Tindakan Sosial.
B. Rumusan Masalah
Guna dapat memberikan alur penjelasan yang baik, maka dibuatlah
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa pengertian dari agama?
2. Bagaimana relasi agama terhadap manusia, masyarakat, dan kebudayaan?
3. Bagaimana peran agama sebagai motivator tindakan sosial?
C. Tujuan Penulisan
Dengan rumusan masalah seperti di atas, maka didapati tujuan penulisan
sebagai berikut:
1. Mengetahui pengertian agama.
2. Mengetahui relasi agama terhadap manusia, masyarakat, dan kebudayaan.
3. Mengetahui peran agama sebagai motivator tindakan sosial.
3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Agama
1. Agama Sebagai Fakta Sosial
Agama dapat ditelusuri hingga ribuan tahun silam. Bahkan, di dalam
agama itu sendiri tak jarang ditemukan ajaran yang menyataka sudah
seberapa lama eksistensi agama itu hadir dunia. Dengan rentang masanya
yang begitu jauh tersebut, maka agama bukanlah hal yang baru dan
merupakan fakta sosial. Lebih jauhnya, fakta sosial menurut para ahli adalah
seperti berikut.
Menurut Dadang Kahmad, fakta sosial berangkat dari asumsi umum
bahwa gejala sosial itu riil dan memengaruhi keadaan individu serta
perilakunya yang berbeda dari karakteristik psikologis, biologis, atai
karakteristik individu lainnya. Lebih lagi, karena gejala sosial merupakan
fakta yang riil, gejala-gejala itu dapat dipelajari dengan metode empiris,
yang memungkinkan satu ilmu tentang masyarakat dapat dikembangkan.
Sebagai suatu gejala sosial, fakta sosial berbeda dengan gejala
individual. Sebagai gejala sosial, ia mempunyai tiga karakteristik utama.
Pertama, fakta sosial bersifat eksternal terhadap individu. Artinya, fakta
sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang
memperlihatkan sifat patut dilihat sebagai sesuatu yang berada di luar
kesadaran lindividu. Kedua, fakta sosial itu memaksa individu. Seorang
individu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, didorong, atau dipengaruhi oleh
pelbagai fakta sosial dalam lingkungan masyarakatnya. Artinya, fakta sosial
mempunyai kekuatan memaksa individu melepaskan kemauannya sendiri
sehingga eksistensi kemauannya terlingkupi oleh semua fakta sosial.
Ketiga, fakta sosial itu bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam
masyarakat. Artinya, fakta sosial itu milik bersama, milik semua individu
yang ada di masyarakat tersebut. Fakta sosial benar-benar bersifat kolektif
4
sehingga pengaruhnya pada individu itu juga merupakan hasil dari
kolektifnya ini.1
Fakta sosial menurut Durkheim, terdiri dari dua macam:
a. Bentuk materiel; yaitu sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan
diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah dari dunia
nyata (external world). Contohnya, arsitektur dan norma hukum.
b. Bentuk nonmateriel; yaitu sesuatu yang dianggap nyata. Fakta sosial
jenis ini merupakan fenomena yang bersifat intersubjektif yang hanya
dapat muncul dalam kesadaran manusia. Contohnya, egoisme,
altruisme, dan opini.
Adapun menurut tipenya, fakta sosial —yang menjadi pusat
perhatian sosiologi— terdiri dari struktur sosial dan pranata sosial. Struktur
sosial adalah jaringan hubungan sosial di mana interaksi sosial berproses
dan menjadi terorganisir. Sehingga dapat dibedakan posisi-posisi sosial dari
individu dan subkelompok. Sedangkan pranata sosial adalah antarhubungan
norma-norma dan nilai-nilai yang mengitari aktivitas manusia —yang
dalam bahasa Inggris disebut institution— seperti keluarga, pemerintahan,
ekonomi, pendidikan, agama, dan ilmu pengetahuan.2
Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, agama termasuk kategori
bentuk nonmateriel dengan tipe pranata sosial. Agama sebagai fakta sosial
sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Dadang Kahmad di atas.
2. Agama dan Religi
Berdasarkan sudut pandang kebahasaan —bahasa Indonesia pada
umumnya— “agama” dianggap sebagai kata yang berasal dari bahasa
sansekerta yang artinya “tidak kacau”. Agama diambil dari dua akar suku
kata, yaitu a yang berarti “tidak” dan gama yang berarti “kacau”. Hal ini
mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang
1 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, Cet. 5,
hlm. 5 2 Ibid., hlm. 6
5
mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Menurut inti maknanya
yang khusus, kata agama dapat disamakan dengan kata religion dalam
bahasa Inggris, religie dalam bahasa Belanda —keduanya berasal dari
bahasa Latin, religio, dari akar kata religare yang berarti mengikat.3
Dilihat dari sudut pandang pemahaman manusia, agama memiliki
dua segi yang membedakan dalam perwujudannya, yaitu sebagai berikut.
a. Segi kejiwaan (psychological state), yaitu suatu kondisi subjektif atau
kondisi dalam jiwa manusia, berkenaan dengan apa yang dirasakan oleh
penganut agama. Kondisi inilah yang biasa disebut kondisi agama, yaitu
kondisi patuh dan taat kepada yang disembah. Kondisi itu hampir sama
dengan konsep “Religius Emotion” dari Emile Durkheim. Emosi
keagamaan seperti itu merupakan gejala individual yang dimiliki oleh
setiap penganut agama yang membuat dirinya merasa sebagai “makhluk
Tuhan”. Dimensi religiositas merupakan inti dari keberagamaan. Inilah
yang membangkitkan solidaritas seagama, menumbuhkan kesadaran
beragama, dan menjadikan seseorang menjadi orang yang saleh dan
bertakwa.
Segi psiologis ini sangat sulit diukur dan susah diamati karena
merupakan milik pribadi pemeluk agama. Pengungkapan
keberagamaan segi psikologis ini baru bisa dipahami ketika telah
menjadi sesuatu yang diucapkan atau dinyatakan dalam perilaku orang
yang beragama tersebut.
b. Segi objektif (objective state), yaitu segi luar yang disebut juga kejadian
objektif, dimensi empiris dari agama. Keadaan ini muncul ketika agama
dinyatakan oleh penganutnya dalam berbagai ekspresi, baik ekspresi
teologis, ritual, maupun persekutuan. Segi objektif inilah yang bisa
dipelajari apa adanya dan, dengan demikian, bisa dipelajari dengan
menggunakan metode ilmu sosial. Segi kedua ini mencakup adat-
istiadat, upacara keagamaan, bangunan, tempat-tempat peribadatan,
3 Ibid, hlm. 13
6
cerita yang dikisahkan, kepercayaan, dan prinsip-prinsip yang dianut
suatu masyarakat.4
Dari uraian tentang definisi agama di atas, dapat disimpulkan sebagai
berikut.
Pertama, sebagian besar ilmuwan membatasi pengertian agama
dalam bentuk yang hanya bisa diterapkan pada agama-agama Samawi yang
masih otentik saja, yakni agama-agama tauhid yang daidasarkan pada
keyakinan tentang adanya Tuhan Yang Maha Pencipta, Maha Mengadakan,
Pemberi bentuk, dan Pemelihara segala sesuatu, serta hanya kepada-Nya
dikembalikan segala urusan. Agama budaya —seperti agama alam yang
hanya berdasar akal ataupun agama-agama yang bertuhankan dunia
binatang, tumbuhan, gejala-gejala alam, atau kekuatan-kekuatan lain di luar
alam— tidak termasuk dalam batasan ini.
Kedua, sebagai kebalikan dari gambaran tentang agama seperti tersebut
di atas, mereka —diantaranya para sosiolog dan arkeolog seperti Emil
Durkheim, pemimpin mazhab ilmu sosial Perancis, dan Solomon Reinach—
menyisihkan ide tentang Tuhan Yang Maha Pencipta. Dalam hal ini mereka
beralasan bahwa setiap agama klasik di Timur —seperti Budha, Jainisme,
dan Kong Hu Cu— semata-mata didasarkan pada etika, tidak memuat unsur
ketuhanan dan ibadah.5
Para ahli sepakat bahwa penguasaan agama hanya didominasi oleh
manusia karena agama merupakan salah satu aspek yang membedakan
manusia dari makhluk lain. Selain itu, hanya manusia yang dianggap
mempunyai dua unsur kehidupan: rohani dan jasmani. Dalam pemenuhan
kebutuhannya, manusia tidak hanya membutuhkan sesuatu yang bersifat
material biologis —seperti makan, minum, kawin, dan bertempat tinggal—
tetapi juga sesuatu yang bersifat rohaniah, seperti rasa bahagia, berbakti,
dan berekreasi.
4 Ibid., hlm. 14 5 Ibid., hlm. 18.
7
Karena agama hanya dimiliki oleh manusia maka dikenal istilah Homo
Religiosus, yaitu tipe manusia yang di suatu alam yang sacral penuh dengan
nilai religius dan dapat menikmati sakralitas yang ada dan tampak di alam
semesta, alam materi, alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, dan alam
manusia. Pengalaman dan pengahayatan terhadap yang suci selanjutnya
memngaruhi, membentuk, dan menentukan corak serta hidupnya. Selain
Homo Religiosus, dikenal juga Homo Non-Religiosus, yaitu manusia yang
tidak berorientasi kepada agama, atau orang yang hidup di alam yang sudah
didesakralisasikan, sudah alamiah, tanpa sakralitas yang dirasa atau dialami.
Bagi manusia Homo Non-Religiosus, kehidupan dan dunia sekitarnyatidak
dianggap sakral lagi; mereka menganggapnya profan.6
B. Agama Dalam Relasi Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan
Manusia, masyarakat, dan kebudayaan berhubungan secara dialektik.
Ketiganya berdampingan dan berimpit saling menciptakan dan meniadakan.
Ketiganya ada secara bersama-sama, berimpit untuk menciptakan relasi makna.
Keberadaan mereka tidak bisa mandiri tanpa berkaitan dengan yang lainnya.
Dalam relasi itu, masing-masing mengalami kehilangan dirinya dalam sebuah
momen untuk kemudian bisa muncul kembali dalam momen yang lain.7
Satu sisi manusia menciptakan sejumlah nilai bagi masyarakatnya, pada
sisi lain secara kodrati manusia senantiasa berhadapan dan berada dalam
masyarakatnya, homo socius. Masyarakat telah ada sebelum individu
dilahirkandan masih aka nada setelah individu mati. Lebih dari itu, di dalam
masyarakatlah dan sebagai hasil proses sosial, individu menjadi sebuah pribadi
ia memperoleh dan berpegang pada suatu identitas. Manusia tidak akan eksis
bila terpisah dari masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat (sebagai kumpulan
individu manusia) diciptakan oleh manusia, dan manusia merupakan produk
6 Ibid., hlm. 19 7 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Potret Agama dalam Dinamika Konflik,
Pluralisme, dan Modernitas), Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 17.
8
dari masyarakat. Kedua hal tersebut menggambarkan adanya dialektika inhern
dari fenomena masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan dialektika sosial.8
Agama dalam konteks budaya berada dalam dialektika ini. Ada
seseorang manusia yang melakukan pemaknaan baru terhadap sistem nilai suatu
masyarakat, lalu mengemukakannya dengan meminjam simbol budaya yang
telah tersedia. Perbedaan agama sebagai produk budaya dengan produk lainnya
—konstruksi rumah atau model berpakaian, misalnya— terletak pada
ketrasendenan yang dihasilkan agama.9
Dengan demikian, agama berasal dari proses objektivasi tertentu yang
bernilai transenden. Sebagai proses objektivasi, di dalamnya melibatkan
hubungan antar subjek (yang dalam hal ini adalah manusia, dan biasanya
bersifat kolektif), kebudyaan (sebagai bentuk eksternal), dan artefak (sebagai
objek ciptaan manusia).10
Teori sosial pada awalnya bersifat historis dan komparatif. Objek
analisisnya berupa suatu kasus tertentu. Dalam sudut teori ini, memahami suatu
masyarakat berarti memahami perbedaannya dengan berbagai bentuk
kehidupan pada masa-masa dan tempat yang berbeda.
Dalam kaitannya dengan kehidupan yang lebih modern setelah usai
Perang Dunia II, terjadi perubahan arus utama tradisi intelektual dalam ilmu
sosial, yaitu berkembangnya “teori modernisasi” yang menerapkan analogi
antara evolusi sosial dan organik. Teori ini menyatakan bahwa munculnya
bentuk-bentuk sosial yang lebih kompleks ditentukan oleh dua proses kembar,
yaitu spesialisasi dan diferensiasi struktural, pada satu sisi dan pada sisi lain
ditentukan oleh mekanisme integrasi dan koordinasi sosial. Untuk mengamati
perubahan sosial yang terus bertambah rumit, teori ini mengemukakan
pengkhususan dalam penilikannya, bahwa teori ilmu sosial harus menilik secara
khusus simbol-simbol kebangsaan dan komunitas yang lebih universal.
Perkembangan simbol-simbol yang lebih universal ini pada gilirannya akan
8 Ibid., hlm. 18. 9 Ibid., hlm. 20. 10 Ibid. hlm. 21.
9
melemahkan ikatan-ikatan sempit keluarga, suku, agama; menghilangkan
potensi perpecahan, serta menyediakan suatu konsensus umum bagi kehidupan
politik.
Akhirnya teori modernisasi merosot ketika konsensus ortodoks yang
mendasari program kerjanya dipertanyakan. Kemerosotannya berkaitan dengan
perkembangan yang lebih luas di dalam dan di luar ilmu-ilmu sosial. Di Barat,
misalnya, konflik seputar masalah ras, gaya hidup, agama, dan gender memberi
kesan pada pengamat bahwa masyarakat modern belum mencapai suatu
“konsesnsus kewargaan” yang kuat seperti diduga. Di dunia ketiga, kekacauan
politik, pertentangan etnis, dan pertumbuhan yang tidak merata mngemukakan
fenomena bahwa perubahan modernisasi hanya teoretis walaupun telah
dilakukan proses-proses pembangunan dan sejenisnya.11
Dengan pemaparan di atas, bukanlah tindakan yang arif
mempermasalahkan aspek-aspek sosial yang bukan menjadi masalah sosial.
Tindakan kompulsif dalam menerepkan keinginan akan kemajuan harus
diimbangi dengan pemeliharaan aspek sosialnya seperti perbedaan ras, gaya
hidup, budaya, dan agama yang bukan bagian dari masalah sosial. Demikian
idealnya, kemajuan menyebabkan aspek-aspek di atas juga terpelihara dan
dapat menghapuskan suatu keadaan negatif yang ditimbulkan dari berbagai latar
belakaang tersebut.
C. Agama Sebagai Motivator Tindakan Sosial
Membicarakan agama dalam fungsinya sebagai motivator tindakan
manusia (sosial), berarti mengulas kembali adanya perbedaan pandangan
tentang definisi agama yang disebabkan perbedaan pemahaman dan
penghayatan seseorang.12
Berbicara masalah agama memerlukan suatu sikap ekstra hati-hati,
karena meskipun masalah agama merupakan masalah sosial, tetapi
penghayatannya amat bersifat individual. Apa yang dipahami dan apa yang
11 Ibid., hlm. 29-30. 12 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama… hlm. 164.
10
dihayati sebagai agama oleh seseorang, sangat bergantung pada latar belakang
dan kepribadiannya. Hal ini membuat adanya perbedaan tekanan penghayatan
dari satu orang ke orang lain, dan membuat agama menjadi bagian yang amat
mendalam dari kepribadian atau privacy seseorang. Oleh karena itu, agama
senantiasa bersangkutan dengan kepekaan emosional. Meskipun demikian,
masih terdapat kemungkinan untuk membicarakan agama sebagai suatu yang
umum dan objektif. Dalam daerah pembicaraan itu diharapkan dapat
dikemukakan hal umum yang menjadi titik kesepakatan para penganut agama,
meskipun hal itu merupakan hal sulit.
Ada berbagai definisi agama yang menunjukkan adanya pemahaman
yang berbeda secara individual. Para ilmuwan Barat yang mengajukan
pendapatnya di antaranya sebagai berikut.
1. Wallace yang mengatakan bahwa agama adalah “suatu kepercayaan tentang
makna terakhir alam raya”.
2. E.S.P Haynes yang berpendapat bahwa agama merupakan “suatu teori
tentang hubungan manusia dengan alam raya”.
3. John Morley yang mengartikan agama sebagai “perasaan-perasaan kita
tentang kekuatan-kekuatan tertinggi yang menguasai nasib umat manusia”.
4. James Martineau yang mendefinisikan agama sebagai “kepercayaan tentang
Tuhan yang abadi, yaitu tentang jiwa dan kemauan Ilahi yang mengatur
alam raya dan berpegang pada hubungan-hubungan moral dengan umat
manusia”.
Dengan demikian, peran agama dalam kehidupan manusia —manusia
modern atau manusia primitif sekalipun— hakikatnya tidak terdapat perbedaan,
yaitu memenuhi kecenderungan alamiahnya, yakni kebutuhan akan akspresi
dan rasa kesucian. Perbedaan mungkin muncul bagi masyarakat modern, yang
menganggap kesucian itu lebih merupakan sesuatu yang terletak dalam daerah
kehidupan mental, spiritual, atau rohani. Dalam kehidupan modern, memang
terjadi kecenderungan untuk mencoba merendahkan arti kehidupan materiel,
11
sehingga kadang terjadi pencampuradukan segi kehidupan rohani dan segi
kehidupan materiel.13
Dalam analisis Weber, kenyataan tersebut merupakan fenomena
sosiologis tentang tingkah laku manusia, yang mengiginkan makna hidup
berupa gagasan tentang tindakan rasional dalam memahami dan menafsirkan
tingkah laku manusia yang dikenal dengan konsep Tipe Ideal dalam
Protestianisme-nya.
Menurut Weber, dalam tindakannya, manusia (sosial) terdiri atas empat
jenis tipe ideal sebagai berikut.
1. Tingkah laku zweckra-tional atau rasional tujuan; yaitu tingkah laku
manusia cita-cita rasional. Bentuk orientasi ini mencakup perhitungan yang
tepat dan pengambilan sarana-sarana yang paling efektif untuk tujuan-
tujuan yang dipilih dan dipertimbangkan dengan jelas, atau sasaran.
Pandangan ini merupakan kerangka pikir yang sangat utilitarian atau
instrumentalis. Kerangka pikir ini logis, ilmiah, dan ekonomis.
2. Bagian kedua dari tindakan manusia (sosial) adalah tingkah laku
wertrational atau rasional nilai. Menurut model ini, seorang pelaku terlibat
dalam nilai penting yang mutlak atau nilai kegiatan yang bersangkutan. Dia
lebih mengejar nilai-nilai daripada memperhitungkan sarana-sarana dengan
cara yang evaluative-netral. Manusia yang mengatakan kebenaran apa
adanya, jelas bertindak secara rasional nilai. Juga semua tingkah laku
manusia yang rasional mengandung sebuah unsur rasionalitas-nilai, karena
pencarian tujuan-tujuan secara logis dalam segala bentuk mengandaikan
bahwa tujuan-tujuan itu dinilai oleh si pelaku.
3. Jenis yang ketiga adalah tipe ideal untuk tindakan afektif atau emosional;
yaitu tingkah laku yang berada di bawah dominasi perasaan secara
langsung. Di sini tidak ada rumusan sadar, nilai-nilai, atau kalkulasi rasional
sarana-sarana yang cocok. Tindakan ini sama sekali emosional dan, karena
itu, tidak rasional.
13 Ibid., hlm. 161-162.
12
4. Kategori selanjutnya adalah tindakan manusia yang ia beri nama
tradisionalis. Ketegori ini mencakup tingkah laku yang berdasarkan
kebiasaan yang muncul dari praktik-praktik yang mapan dan menghormati
otoritas yang ada. Jenis tingkah laku ini tidak bisa dianggap cukup sebagai
tingkah laku yang “dimaksudkan” dan sebagai “tindakan sejati”. Weber
juga memperhitungkan intensionalitas sebagai sesuatu yang implisit dan
relatif berada di bawah sadar. Dalam segi ini, tindakan tradisionalis
bukannya tidak sama dengan tindakan afektif.
Keempat jenis tindakan sosial itu merupakan cara-cara individu
memberi makna pada tindakan mereka dan itu merupakan kodrat manusia yang
berusaha memberi arti tertentu kepada hidupnya. Oleh karena itu, manusia
adalah suatu makhluk religius; bahkan kegiatan-kegiatan ekonomisnya
mengandaikan pandangan dunia umum tertentu yang ia pakai untuk membuat
kehidupannya dapat dipahami.14
Ilustrasi lain diungkapkan oleh Nurcholis Madjid dengan mengambil
penyebab terjadinya perang dengan motif agama. Menurutnya, sebelum zaman
industri, perang sering terjadi karena dorongan agama. Setelah zaman industri
tiba, perang seringkali didorong oleh rebutan harta. Ia melanjutkan, “Kita tidak
dapat begitu saja menilai bahwa perang atas nama agama adalah lebih mulia
daripada perang atas nama harta, kecuali jika kita termasuk dan ada dalam pihak
golongan agama yang berperang itu sendiri.
Jika berada dalam agama ketiga, di luar kedua agama yang sedang
berperang, kita akan tersenyum mengejeknya karena memandang peperangan
yang terjadi antara dua agama —yang bukan agama kita— adalah suatu ironi
dan tragedy, karena merupakan usaha saling menghancurkan oleh kedua belah
pihak yang (dalam pandangan kita) sama-sama palsu (karena kedua agama itu
bukan agama kita dan tidak seperti agama kita). Jadi, perang itu adalah suatu
perang atas nama kepalsuan, dan kedua belah pihak tidak masuk akal untuk
berperang.
14 Ibid., hlm. 163-164.
13
Tetapi apabila kita termasuk dan berada di pihak suatu agama yang
berperang dengan agama lain, dengan sendirinya perang itu adalah perjuangan
sebuah kebenaran untuk melawan dan menghancurkan kepalsuan. Adakah nilai
hidup yang lebih tinggi daripada perjuangan menegakkan kebenaran melawan
kepalsuan? Kita pun akan meyakini adanya unsur kesucian dalam perang serupa
itu, sehingga mati di dalamnya dianggap kehormatan yang besar debagai syahid
atau martir.15
Untuk itu, agar tidak terjebak pada pemahaman agama yang sempit,
alangkah baiknya jika kita kembali kepada penegasan Nabi Muhammad saw.
yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya agama di sisi Allah adalah al-
hanifiyyat al-samhah; semangat kebenaran yang lapang dan terbuka; agama
yang bersemangta kebenaran dan lapang serta terbuka untuk menolong
manusia. Jika saja semangat yang demikian itu diterapkan pada tataran
kehidupan sehari-hari, agama bisa jadi mendorong semangat bagi setiap
tindakan sosial.16
Menurut Beni Ahmad Saebani, kelompok sosial memiliki tujuan yang
sama. Mereka merasa, bahwa dalam kelompok itulah tujuan dapat dicapai.
Tujuan yang ada diperkuat oleh keyakinan atas ajaran agama, suatu keyakinan
yang berisikan penjelasan dan petunjuk untuk memahami gejala-gejala dan
pengalaman-pengalaman, serta penjelasan yang menghasilkan kehidupan
rasional dan kenyataan hidup yang dialami manusia yang irrasional. Kelompok
beragama menerima berbagai realitas. Kehidupan adalah riil, nyata, dan jelas,
tetapi dalam mengarungi kehidupan tidak semua yang riil dapat dirasionalisasi.
Keyakinan orang beragama, bahwa umur, rezeki, dan jodoh ada di tangan Tuhan
adalah riil, meskipun ketiganya tidak dapat dipastikan oleh manusia.17
Prilaku sosial yang merujuk pada ajaran agama yang ditopang oleh
sistem ritual dan tujuan ideal dalam beragama, sesungguhnya dimanifestasikan
15 Ibid., hlm. 165. 16 Ibid., hlm. 166. 17 Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Agama: Kajian tentang Perilaku Institusional dalam
Beragama Anggota Persis dan Nahdlatul Ulama, Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm.
6.
14
ke dalam bentuk perilaku institusional. Karenanya, sifat dan karakteristik
perilaku ini lebih bergantung pada fakta sosial institusional daripada pada
sumber ajaran agama itu sendiri. Di lain pihak, perilaku institusional dalam
kehidupan sosial keagamaan memasung dinamika intelektual dan dinamika
kultural setiap individu yang merupakan potensi eksternal dalam institusi
bersangkutan. Dalam bahasa lain, perilaku individu akan dipandang
konfrontatif bila dipaksakan memasuki wilayah perilaku kolektif institusional.
Loyalitas dan komitmen yang demikian akan diragukan dan secara interaksional
terjadi keterasingan individual dan deniasi kultural.18
Dalam Islam, bangunan teoretis yang digunakan dalam kerangka
berpikir ini dapat dikonseptualisasikan melalui penjelasan konsep berikut.
1. Institusionalisasi yang dimaksud adalah proses pelestarian perilaku secara
structural dan terorganisasi dengan proses interaksi yang terus-menerus
sehingga menjadikan perilaku bersangkutan mendarah daging
terinternalisasi melalui berbagai simbol-simbol yang dimaknai dan
dipahami secara dialogis praktis oleh pelakunya yang ada dalam wadah atau
organisasi keagamaan yang sama.
2. Perilaku sosial keagamaan adalah tindakan-tindakan yang berkaitan
dengan segala perbuatan yang secara langsung berhubungan atau
dihubungkan dengan nilai-nilai ajaran dan tuntunan agama Islam atau yang
menjadi keputusan institusi.
3. Pemahaman keagamaan yang dimaksud adalah pendekatan yang
digunakan untuk menggali kandungan makna, hukum, maksud-maksud, dan
isyarat yang terdapat dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an dan
Al-Sunnah atau pendapat ulama yang dipandang sejalan dan sepaham atau
representasi dari seluruh cara pandang umat Islam yang berada dalam tubuh
yang sama.
4. Interaksi umat Islam artinya tindakan yang saling berhubungan di antara
individu atau perilaku yang diintegrasikan secara structural ataupun kultural
18 Ibid., hlm. 8
15
sehingga tindakan tersebut menjadi simbol budaya yang terisntitusikan dan
tidak banyak membutuhkan penafsiran ulang atau secara relatif mutlak
disepakati dan menjadi sandaran perilaku bagi generasi berikutnya di
kalangan anggota organisasi keagamaan tertentu.
5. Ulama, kyai, dan ustadz yang dimaksud adalah tokoh agama yang
dipandang mampu dan professional dalam menyelesaikan berbagai masalah
keagamaan, baik masalah ritual maupun sosial. Ulama, kyai, dan ustadz
hierarkisnya jelas. Ustadz sebagai guru yang mengajar di pesantren tidak
serta merta kyai atau ulama, tetapi ulama dan kyai biasanya sekaligus
sebagai ustadz. Ustadz yang dikategorikan setingkat kyai adalah ulama yang
memiliki kapabilitas keilmuan yang diakui oleh komunitas tertentu.
Sebagaimana seorang pengasuh pondok pesantren atau mubaligh, yang
tingkat jam terbangnya dalam berceramah cukup tinggi dan popularitasnya
meluas akan dipanggil kyai oleh komunitas muslim tertentu karena
dipandang memiliki ilmu yang luas dan tinggi, serta profesional, misalnya
ahli dalam bidang ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu falak, ilmu ushul fiqh, ilmu
Bahasa Arab, ilmu fiqh, dan seorang mujtahid.19
Sedangkan interaksi antarumat beragama diarahkan oleh ajaran-ajaran
agama itu sendiri sehingga kemungkinan diarahkan oleh norma-norma yang
berlaku sangat dominan. Tradisi dan kebudayaan lokal dapat diartikan juga
sebagai salah satu penganut agama dengan label organisasi masyarakat dan
keagamaan tempat pemeluk agama itu beraktivitas. Adaptabilitas dalam
perilaku keagamaan sengaja dibentuk atau terbentuk karena interaksi yang satu
arah. Proses mengarahkan perilaku sehingga menjadi homogeny adalah bagian
dari visi dan misi dalam lembaga keagamaan.20
19 Ibid., hlm. 25. 20 Ibid., hlm. 29.
16
BAB III
PENUTUP
A. Simpulan
Sebagaimana yang telah diulas pada bab I dan II, maka didapati rumusan
simpulan sebagai berikut.
1. Agama merupakan gejala sosial yang menjadi fakta sosial. Berdasarkan
sudut pandang kebahasaan —bahasa Indonesia pada umumnya— “agama”
dianggap sebagai kata yang berasal dari bahasa sansekerta yang artinya
“tidak kacau”. Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu a yang berarti
“tidak” dan gama yang berarti “kacau”. Hal ini mengandung pengertian
bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia
agar tidak kacau.
2. Manusia, masyarakat, dan kebudayaan berhubungan secara dialektik.
Ketiganya berdampingan dan berimpit saling menciptakan dan meniadakan.
Ketiganya ada secara bersama-sama, berimpit untuk menciptakan relasi
makna. Keberadaan mereka tidak bisa mandiri tanpa berkaitan dengan yang
lainnya. Dalam relasi itu, masing-masing mengalami kehilangan dirinya
dalam sebuah momen untuk kemudian bisa muncul kembali dalam momen
yang lain.
3. Berbicara masalah agama memerlukan suatu sikap ekstra hati-hati, karena
meskipun masalah agama merupakan masalah sosial, tetapi penghayatannya
amat bersifat individual. Apa yang dipahami dan apa yang dihayati sebagai
agama oleh seseorang, sangat bergantung pada latar belakang dan
kepribadiannya. Hal ini membuat adanya perbedaan tekanan penghayatan
dari satu orang ke orang lain, dan membuat agama menjadi bagian yang
amat mendalam dari kepribadian atau privacy seseorang. Oleh karena itu,
agama senantiasa bersangkutan dengan kepekaan emosional.
17
B. Saran
Penulis menyadari akan keterbatasan makalah yang disusun, baik dari
segi isi maupun relevansinya. Oleh karena itu penulis mengajukan saran
lanjutan sebagai berikut.
1. Dalam hal agama sebagai motivator tindakan sosial, pemahaman harus
dilanjutkan pada tingkat penyampaian kepada khalayak tentang identifikasi
nilai-nilai agama sebagai fator penggerak tindakan sosial.
2. Diperlukan kajian lebih lanjut.
3. Diperlukan tambahan pengetahuan dari ulasan pakar sosiologi agama yang
relevan dengan konteks kekinian, utamanya dalam menghadapi radikalisme
agama yang semakin menggejala.
DAFTAR PUSTAKA
Kahmad, Dadang. Sosiologi Agama (Potret Agama dalam Dinamika Konflik,
Pluralisme, dan Modernitas). Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
————— Sosiologi Agama. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009. Cet. 5.
Saebani, Beni Ahmad. Sosiologi Agama: Kajian tentang Perilaku Institusional
dalam Beragama Anggota Persis dan Nahdlatul Ulama. Bandung: PT
Refika Aditama. 2007.