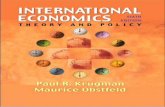1. Sistem Peradilan di Indonesia. - Digilib UNS
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 1. Sistem Peradilan di Indonesia. - Digilib UNS
25
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.
A. TINJAUAN PUSTAKA
1. Sistem Peradilan di Indonesia.
a. Sejarah Singkat Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.
1) Masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda
Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kekuasaan
kehakiman dilaksanakan oleh empat badan Peradilan yang dalam
bahasa Belanda dikenal dengan istilah rechtspraaken, peradilan
yang dimaksud terdiri dari:49
(1) Peradilan Gubernemen (Gouvernements rechtpraak) yang
meliputi seluruh Hindia Belanda.
(2) Peradilan Pribumi (Inheemscherecht-spraak) hanya terdapat di
daerah langsung (administratif) daerah seberang.
(3) Peradilan Swapraja (Zelfbestuurs rechtspraak) yang terdapat di
daerah tidak langsung (otonom), kecuali daerah Swapraja Paku
Alaman dan Pontianak.
(4) Peradilan Desa (Dorps rechtspraak), dengan catatan, di
samping yang berdiri sendiri ada yang merupakan bagian dari
Peradilan Gubernemen, Peradilan Swapraja, maupun Peradilan
Adat.
Pada masing-masing jenis Peradilan itu, dimungkinkan pula
adanya sejenis kamar berupa Kamar Peradilan Agama
(Godsdienstige Rechtspraak).
2) Masa Penjajahan Jepang
Pertama-tama dibentuk oleh pemerintah militer Jepang adalah
peradilan yang melindungi militer yang disebut Gunritukaigi.
Pembentukannya didasarkan pada Osamu Gunrei Nomor 2/1942,
49 Koerniatmanto Soetoprawiro, Pemerintahan dan Peradilan Indonesia: Asal-Usul dan
Perkembangannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 91-92
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
26
sementara sebelumnya dengan Osamugunrei Nomor 1/1942 telah
diatur tentang jenis-jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.
Seiring dengan itu Gunritukaigi berwenang mengadili tindak
pidana yang pada pokoknya dikualifisir sebagai kejahatan yang
bersifat menggangu, menghalang-halangi dan melawan Bala
tentara Jepang. Jenis hukuman dapat berupa: pidana penjara,
pidana pembuangan, pidana denda dan pidana mati. Osamu Gunrei
Nomor 1/1942 membenarkan penjatuhan pidana kumulatif yaitu
penjatuhan bersama-sama atau penggabungan antara pidana
penjara ditambah pembuangan. Juga dapat dikenakan hukuman
tambahan berupa perampasan. Dengan UU tanggal 2 Maret 1942
(UU Nomor Istimewa) pidana mati dapat juga dijatuhkan terhadap
perbuatan pidana yang berupa perusakan atau perampasan barang
atau alat maupun sarana yang dipergunakan oleh atau berhubungan
dengan tentara Jepang seperti parit-parit, perkebunan, sumber
minyak, jalan, telepon, pos dan lain-lain.50
Selain peradilan yang bersifat melindungi kepentingan milter,
dengan UU Nomor 14 Tahun 1942 kemudian diubah dengan UU
Nomor 34 tahun 1942 dibentuklah Gunsei Hoin yaitu Pengadilan
Pemerintah Balatentara dan Gunsei Kensatu Kyoku atau
Kejaksanaan Pemerintah Balatentara. Kedua Undang-undang itu
merupakan peraturan dasar bagi pembentukan organisasi peradilan
di Jawa dan Madura. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Nomor
1 tahun 1942, pada prinsipnya organisasi dan struktur badan
peradilan sama dengan organisasi dan struktur badan peradilan
sebelumnya yang berlaku pada masa Hindia Belanda dengan di
sana sini diadakan perubahan seperlunya. Perubahan yang
mendasar adalah:
50 Mertokoesoemo, 1971, hlm. 11-13 dalam Bahder Johan Nasution, Sejarah Perkembangan
Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014 ,
hlm. 23.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
27
(1) Dihapuskannya perbedaan antara peradilan Gubernemen dan
Peradilan Bumi Putera;
(2) Hakim untuk golongan Eropa dihapuskan;
(3) Hakim untuk golongan Bumi Putera kekuasaannya diperluas
sehingga meliputi semua golongan;
(4) Penghapusan kewenangan mengadili pada tingkat pertama dari
Raad van Justitie dan Hooggerechtshof;
(5) Penghapusan peradilan Residentiegerecht;
(6) Perubahan istilah-istilah badan peradilan seperti “Landraad”
menjadi Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri), “Landgrecht”
menjadi Keizei Hooin (Hakim Kepolisian), “Regent
Schapsgercht” menjadi Gun Hooin (Pengadilan Kawedanan),
“Hof voor Islamietsche Zaken” menjadi Kaikyoo Kootoo Hooin
(Mahkamah Islam tinggi), “Priesterraad” menjadi Sooryoo
Hooin (Rapat Agama).
Untuk daerah di luar Jawa dan Madura kondisi seperti itu
baru diberlakukan pelaksanaannya berupa Timo Seirei Otsu Nomor
40 Tahun 1943 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1944.51
3) Kekuasaan Kehakiman Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sejak berlakunya UUD 1945 (tanggal 18 Agustus 1945) hingga
kini telah disahkan berikut perubahan Undang-undang yang
mengatur kekuasaan kehakiman, yaitu: UU Nomor 19 Tahun 1948,
UU Nomor 19 Tahun 1964 dan UU Nomor 14 Tahun 1970
sebagaimana dirobah dengan UU No.35 Tahun 1999, Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
yang terakhir Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman adalah Ketiga UU itu diciptakan dalam
rangka untuk memenuhi perintah Pasal 20, 21, 24 dan Pasal 25
UUD 1945. Sebelum berlakunya UU Nomor 19 Tahun 1948
sepanjang menyangkut peraturan-peraturan dan badan-badan atau
51
Mertokoesoemo, Op.Cit. hlm. 24
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
28
institusi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman berlaku
peraturan-peraturan dan badan-badan sebelum kemerdekaan (masa
Jepang dan Belanda). Keberlakuan semacam itu didasarkan pada
ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang pada intinya
mengatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada
masih terus berlaku selama belum diadakan yang baru menurut
Undang-undang Dasar.
b. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat.
Kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen keempat
merupakan kekuasaan merdeka yang dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan
Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata
Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
Sebagai suatu perbandingan, perjalanan sejarah kekuasaan
kehakiman dalam Islam menunjukkan bahwa kekuasaan yudikatif
yang sudah dilaksanakan oleh beberapa lembaga—yang masing-
masing berkuasa dalam bidangnya, tetapi bersatu di bawah satu
kekuasaan umum. Pada dinasti Umayyah, kekuasaan kehakiman
menyebutnya lembaga pelaksana hukum (Nizam al-Qadha`),
sedangkan pada masa Dinasti Abbasiyah menyebutnya lembaga yang
bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum (Nizham al-
Mazhalim).52
Kesemuanya itu adalah untuk menegakkan ketertiban
umum, baik di lingkungan pemerintahan, maupun di lingkungan
masyarakat. Meskipun kedua dinasti tersebut berbeda penggunaan
peristilahan untuk pelaksana kekuasaan kehakiman, akan tetapi
masing-masing badan yang berada di bawahnya sama-sama memiliki
52
Jaenal Arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Fajar
Interpratama Offset, 2008, hlm 170.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
29
tiga badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yakni
Wilayah al-Qadha`, Wilayah al-Hisbah, dan Wilayah al-Mazhalim.
Bahkan pada Dinasti Mamluk terdapat satu pelaksana kekuasaan
kehakiman lagi, yakni Mahkamah Militer (Mahkamah al-
Asykariyah), dan kesemua lembaga tersebut berada di bawah naungan
al-Qadhi al-Qudha`-semacam Mahkamah Agung di Indonesia yang
membawahi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.53
c. Fungsi dan Peran Lembaga Pengadilan di Indonesia.
Pengadilan sesungguhnya merupakan suatu institusi dalam
masyarakat yang telah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat,
tidak hanya sebagai lembaga hukum yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu
institusi ekonomi dan politik serta sebagai lambang harapan-harapan
masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan lain-lain. Pengadilan
tidak dapat dipandang hanya sebagai suatu institusi hukum saja sebab
sama sekali tidak tergambarkan secara lengkap.54
Pengadilan nasional
di negara berkembang seperti halnya Indonesia, dianggap identik
dengan sistem ekonomi, hukum, budaya dan politik dari negara-
negara tempat pengadilan tersebut berada.55
Pengadilan sebagai lembaga pelaksana dari kekuasaan
kehakiman sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting,
keberadaan lembaga pengadilan merupakan ciri utama dari sebuah
negara hukum. Barda Nawawi menyebutkan bahwa peranan
pengadilan jika dikelompokkan, ada peran yuridis formal dan peran
yuridis materiil. Undang- Undang Dasar membuka peluang untuk
kedua peranan ini sebab lembaga peradilan dalam tatapan konstitusi
53 Lomba Sultan, Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia, Jurnal Al-
Ulum, Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013, hlm.437. 54
Satjipto Rahardjo, Majalah Hukum dan Pembangunan, No. 5 Tahun XXXIV, 1994, hlm. 447. 55
Julian D.M. Lew, Applicable Law in International Commercial Arbitration, Netherlands
Sijthoff and Norhoff, 1978, hlm. 12.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
30
merupakan lembaga sentral yang tidak saja bertanggunjawab dalam
upaya penegakan hukum, melainkan Pula bertanggunjawab di dalam
melindungi, mendamaikan, mencerdaskan dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat.56
Joseph Raz, menjelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan
norma hukum secara efektif, maka diperlukan organ hukum, dalam
hal ini adalah lembaga peradilan.57
Sesuai dengan konstitusi,
pengadilan dapat berperan baik secara politis, yuridis maupun
sosiologis.
(1) Peran politis merupakan fungsi umum dari setiap lembaga negara.
Peran ini meliputi keterlibatan Mahkamah Agung yang secara
sadar membawa negara ini menuju pada tujuan seperti tercantum
dalam konstitusi.58
Peran Mahkamah Agung tersebut tentu saja
harus diikuti oleh lembaga-lembaga pengadilan di bawahnya;
(2) Peran yuridis merupakan fungsi utama dari pengadilan
sebagaimana sebagaimana dikehendaki oleh Pasal l Undang-
undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara
Hukum Republik Indonesia;
(3) Peran sosiologis mempakan peran yang tidak kurang pentingnya
dalam menjalankan kehidupan pengadilan, karena peran ini
merupakan jiwa bagi peran-peran lainnya sebagaimana
dikehendaki oleh Pasal 28 ayat (l) Undang-undang No. 4 tahun
2004 di mana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Semua peradilan di seluruh wilayah lndonesia adalah peradilan
negara dan ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan yang
56 Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebikjasanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 7 57
Joseph Raz, The Concept of Legal System, Oxford University Press, Oxford, 1997, hlm. 92 58
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 1
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
31
menduduki tempat yang tertinggi sistem peradilan kita adalah Mahkamah
Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Ada 4 (empat) lingkungan
peradilan negara yang kesemuanya berpuncak pada Mahkamah Agung.
Empat lingkungan peradilan itu dapat bagi menjadi dua yang bersifat
umum yaitu lingkungan peradilan umum ( peradilan dengan general
jurisdiction) dan yang bersilat khusus (peradilan special jurisdiction)
yaitu lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan
lingkungan peradilan tata usaha negara. Disebut sebagai peradilan
umum karena peradilan umum ini diperuntukkan bagi semua warga
masyarakat tanpa membedakan golongan atau agama, yustisiabele atau
pencari keadilannya umum, setiap orang. Di dalam peradilan umum
masih dikenal spesialisasi seperti peradilan ekonomi. Peradilan khusus
disediakan bagi yustiabele atau pencari keadilan yang khusus (beragama
Islam atau militer) atau yang menggunakan hukum materiel khusus
(hukum pidana militer, hukum Islam).
Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa Mahkamah Agung
sebagai lembaga pengadilan tertinggi mempunyai beberapa fungsi atau
tugas antara lain sebagai berikut.59
1) Pertama, Mahkamah Agung mempunyai fungsi peradilan (yustisiel).
Mahkamah Agung sebagai badan kehakiman, yang melakukan
kekuasaan kehakiman, menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas
pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan serta
menyelesaikan setiap perkara;
2) Kedua, yaitu memimpin peradilan dalam pembinaan dan
pengembangan hukum dan sekaligus mengembangkan hukum
Indonesia melalui putusan-putusannya ke arah kesatuan hukm dan
peradilan;
59
Sudikno Mertokusumo, Sistem Peradilan di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 9 No.6, Tahun 1997,
hlm. 5.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
32
3) Fungsi Mahkamah Agung yang ketiga adalah mengatur. Mahkamah
Agung berwenang untuk menentukan penyelesaian suatu persoalan
yang belum diatur acaranya;
4) Fungsi yang keempat adalah sebagai penasihat;
5) Fungsi yang kelima adalah fungsi pengawasan;
6) Fungsi yang keenam adalah fungsi administratif.60
Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Mahkamah Agung memiliki
peranan yang sangat penting dalam penegakan keadilan di lingkungan
peradilan. Mahkamah Agung secara internal memiliki wewenang untuk
mengawasi tingkah laku para hakim, jalannya persidangan, pekerjaan
pengadilan, penasehat hukum dan notaris di semua lingkungan peradilan.
Dalam konteks pengawasan internal ini, maka tugas pengawasan MA
terhadap para hakim sangat nampak dalam pasal 32 Undang-Undang No. 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dijelaskan bahwa: Mahkamah
Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelengaraan
peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan
kehakiman (ayat (1); Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan
perbuatan para hakim di semua lingkungan lingkungan peradilan dalam
menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, MA juga memiliki wewenang
untuk meminta keterangan tentang hal – hal yang bersangkutan dengan
teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan ayat (2) dan (3) dan
Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan
60 Secara khusus, MA dalam konteks pengawasan tugas hakim, memiliki peran penting sebagai
pengawas internal. Dikatakan pengawas internal karena Mahkamah Agung juga adalah seorang
hakim yang diangkat melalui jalur karier kehakiman dan juga jalur non karier. Mahkamah
Agung adalah lembaga pengawasan internal yang memegang fungsi kontrol dari dalam
terhadap kinerja hakim agar sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar. Mahkamah Agung
adalah pengadilan tertinggi dan melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan.
Sagala menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi di bidang peradilan
belaka, melainkan mempunyai fungsi-fungsi lain. Jadi jika disimpulkan maka Mahkamah
Agung mempunyai beberapa fungsi, yakni: Fungsi peradilan (justitiele functie); Fungsi
pengawasan (Toeziende functie); Fungsi mengatur (Regelende functie); Fungsi penasihat
(Advieserende functie); dan Fungsi administratif (Administratieve functie
Lihat:Budiman B. Sagala, Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Gahlia
Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 157-158.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
33
yang di pandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan
(ayat (4).
Terkait dengan perkembangan fungsi Mahkamah Agung di Amerika
Serikat (Supreme Court) Richard Pacelle menyebutkan bahwa Supreme
Court di era modern telah berfungsi sebagai pembuat kebijakan,
sebagaimana ditulis dalam bukunya “The Supreme Court in a Separation
of Powers System”:
The Supreme Court has become a major policy maker. The Court
made policy from its fi rst decision even when it wore the accurate
moniker, “the least dangerous branch.” But as the central
government increasingly grew in power and authority, its branches
had a concomitant growth of power.
The constitutional independence of the Court was predicated on a
passive, limited judiciary that filled in the gaps rather than an
activist policy leader. The modern Supreme Court is a policy
maker that is actively engaged in virtually every area of law, but it
is actually the dominant leader in the subset issues that involve
individual liberties and civil rights.61
Jeffrey A. Segal, Harold J. Spaeth, Sara C. Benesh juga
mengatakan hal sama sebagai berikut.
We live in a democracy, but within that democracy we give judges
broad discretion to determine, for instance, whether abortions should
be allowed, death penalties inflicted, homosexuality criminally
punished, and, every century or so, who should be president.4 All
judges make policy; at the top of the judicial policy-making pyramid
rests the United States Supreme Court.62
d. Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri.
Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa permasalahan yang
timbul di dalam tubuh pengadilan di Indonesia adalah: (a) Masalah
penegakan hukum, bagi kepentingan pencari keadilan; (b) Masalah
penegakan hukum dalam ruang lingkup departemen; (c) Masalah
bertumpuknya perkara di Mahkamah Agung. Masalah di atas
61
Richard Pacelle, The Supreme Court in a Separated of Powers System, Routledge, New York,
2015, hlm. 252. 62
Jeffrey A. Segal, Harold J. Spaeth, Sara C. Benesh, The Supreme Court in American Legal
System, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, hlm. 4
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
34
memperlihatkan masih lemahnya penegakan hukum, sehingga perlu
mendapatkan perhatian yang khusus dari aparat penegak hukum,
karena melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi
kenyataan, yaitu tindakan nyata aparat penegak hukum terhadap
pejabat-pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan
melanggar hukum lainnya.63
Sudikno Metokusumo menyatakan bahwa sebagai salah satu ciri
negara hukum, maka kekuasaan kehakiman harus dijamin secara
konstitusional.64
Negara Repblik Indonesia telah memberikan
jaminan konstitusional pada kekuasaan kehakiman yaitu pada Pasal
24 UUD RI 1945. Dalam konteks struktur pengadilan di Indonesia,
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan
bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Dengan menempatkan Mahkamah Agung sebagai puncak
peradilan, maka pembentuk Undang-Undang menghendaki adanya
kesatuan peradilan. Meskipun dengan adanya Mahkamah Konstitusi,
di samping Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan
kehakiman menyebabkan tejadinya dualisme kekuasaan kehakiman
di Indonesia, namun kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh
Mahkamah Agung dan keempat lingkungan di bawahnya masih
terdapat kesatuan peradilan ( eenheid van rechtspraak).65
Membicarakan tentang sistem peradilan di Indonesia, tidak akan
mampu terlepas dari pembahasan tentang kekuasaan kehakiman yang
mandiri yang berujung kepaa kemandirian serta independensi hakim.
Mandiri atau tidaknya kekuasaan kehakiman mempunyai implikasi
yang besar terhadap penegakan hukum yang dilakukan di muka 63
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm.145. 64
Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia, dan
Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm. 2 65
Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Sistem Peadilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI
Menurut UU No. 4 Tahun 2004, Mimbar Hukum, Volume 22 Nomor 1, Februari 2010, hlm.
198.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
35
pengadilan. Kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam arti bebas
dari campur tangan dan pengaruh dari pihak-pihak lain di luar
kekuasaan kehakiman. Putusan dijatuhkan relatif dapat diterima dan
lebih adil bagi para pihak yang berperkara. Sebaliknya kekuasaan
kehakiman yang tidak mandiri dalam proses peradilannya karena
pengaruh campur tangan dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan
kehakiman, maka putusan-putusan yang dihasilkan cenderung
subjektif dan ada unsur keberpihakan kepada sala satu pihak yang
berperkara. Dengan demikian putusan-putusannya pun akan
dirasakan relatif kurang adil dan merugikan salah satu pihak. Bagi
hakim, implikasinya besar, karena sikap hakim dalam proses
persidangan akan amat menentukan objektivitas dalam memutuskan
suatu perkara dan berdampak kepada kualitas putusan.
M. Yahya Harahap menggunakan terminologi “kebebasan relatif
menerapkan hukum.” Terminologi tersebut bermakna kebebasan
hakim tidak mutlak, tetapi bersifat relatif. Untuk itu, langkah yang
ditempuh atau patokan yang dipakai, yaitu: 1) hakim terikat
mengutamakan penerapan ketentuan undang-undang (statute law
must prevalli); 2) boleh melakukan contra legem, 3) bebas
melakukan penasiran.66
Dalam hal kemandirian hakim, ada faktor-faktor yang
memperngaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan
fungsinya. Pada prinsipnya faktor-faktor yang berpengaruh tersebut
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor
eksternal.67
(1) Faktor Internal
Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi
kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan
66
M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 857-858 67
Michael Brayn Rompas, Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Lex
Administratum, Vol.I/No.3/Jul-Sept/2013 hlm. 29.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
36
wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu
sendiri. Jadi faktor internal di sini adalah segala hal yang
berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu
sendiri, yaitu mulai dan rekrutmen/seleksi untuk diangkat
menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim.
Faktor ini berpengaruh, karena secara ungsopmal kekuasaan
kehakiman dilakukan terutama oleh para hakim.
(2) Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang datangnya
dari luar dari diri hakim, terutama berkaitan dengan sistem
peradilan atau sistem penegakan hukumnya. Adapun faktor-
faktor eksternal yang berpengaruh meliputi hal-hal sebagai
berikut :
(a) Peraturan perundang-undangan
Dalam perkembangannya UU No. 14 Tahun 1970 sekarang
digantikan dengan UU Kekuasaan Kehakiman yang baru
yaitu UU No. 4 Tahun 2004 dan perubahannya dalam UU
No. 48 Tahun 2009. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman
baru pembinaan kekuasaan kehakiman sudah diletakkan
dibawah satu atap tetapi dengan puncak ganda, yaitu
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
(b) Adanya intervensi terhadap proses peradilan
Dalam praktek peradilan, memang sulit dihindarkan
adanya intervensi atau campur tangan dari pihak lain,
seperti pemerintah dan pihak ekstra yudisial lainnya.
Campur tangan juga dapat dilakukan oleh pengadilan
atasan, para pencari keadilan atau kuasanya serta
pendukungnya.
(c) Hubungan hakim dengan penegak hukum lain.
Hubungan yang terlalu akrab dan pribadi antara Hakim
dengan penegak hukum lain, seperti Jaksa dan Pengacara,
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
37
dapat menyulitkan hakim dalam menjaga obyektivitasnya,
ketika mereka dihadapkan dalam perkara yang sama.
Demikian pula hubungan hakim dengan pihak lainnya yang
terlalu akrab, dapat pula berakibat yang sama, yaitu sulit
untuk bersikap obyektif.
(d) Adanya berbagai tekanan
Tekanan yang dialami hakim dapat berupa tekanan mental,
fisik, ekonomi dan sebagainya. Sudikno Mertokusumo,
menyatakan sesudah tahun 1970 mulai terasa adanya
tekanan-tekanan pada hakim yang dibuktikan dengan
adanya surat sakti dan telepon sakti, sehingga
menghasilkan putusan-putusan yang bersifat memihak.68
(e) Faktor kesadaran hukum
Faktor kesadaran hukum dapat berpengaruh pula terhadap
jalannya proses peradilan. Kesadaran hukum di sini
meliputi kesadaran hukum masyarakat, pencari keadilan
dan penegak hukum. Apabila semua elemen masyarakat
tanpa kecuali mempunyai tingkat kesadaran hukum yang
tinggi, maka peristiwa rekayasa, kolusi, suap dan mafia
peradilan tidak akan terjadi. Dengan demikian kemandirian
hakim juga otomatis terjaga dengan baik.
(f) Faktor sistem pemerintahan (politik)
Faktor sistem pemerintahan (politik) yang dipakai dapat
juga berpengaruh terhadap institusi peradilan. Ketika sistem
politik Demokrasi Terpimpin berkuasa, maka sistem
peradilan yang dikehendaki juga “sistem peradilan
terpimpin”, sehingga sangat membelenggu
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang mandiri,
bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.
68 Sudikno Mertokusumo, Mewujudkan Sistem dan Proses Peradilan Indonesia yang Bersih dan
Berwibawa, diskusi panel di Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, 16 Mei 1998
dalam Michael Brayn Rompas, Loc. Cit. hlm. 30.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
38
Di bawah sistem pemerintahan orde baru yang kemudian
digantikan sistem pemerintahan orde reformasi, UU No. 19
Tahun 1964 sudah dicabut dengan UU No. 14 Tahun 1970,
yang menjamin adanya kemerdekaan kekuasaan
kehakiman, meskipun harus diakui masih ada beberapa titik
kelemahan, seperti adanya dualisme kekuasaan kehakiman
dan masalah “judiciel review” (hak uji materiil terhadap
Undang-Undang). Dan sekarang UU No. 14 Tahun 1970
sudah digantikan dengan UU No. 4 Tahun 2004 dan
perubahannya dalam UU No. 48 Tahun 2009. Hal di atas
membuktikan bahwa sistem politik/pemerintahan yang
berlaku akan berpengaruh terhadap kemandirian kekuasaan
kehakiman.
e. Tugas Hakim dalam Peradilan Perdata
Putusan Hakim sebagai perwujudan hukum dipengaruhi antara
lain oleh kaidah-kaidah hukum dan tafsirannya, terefleksi dalam
pertimbangan-pertimbangan atau penalaran (reasoning) hakim
sehingga sampai pada sebuah putusan hakim. Proses pengambilan
putusan oleh hakim senantiasa berada dalam situasi tarik menarik
antara dua tuntutan yang seringkali berlawanan, yaitu kehendak untuk
mewujudkan kepastian hukum dan kehendak untuk mewujudkan
keadilan.69
Dalam menjalankan tugasnya, pada hakekatnya dari seorang
hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang salah tidaknya
seseorang atau benar tidaknya peristiwa yang disengketakan dan
kemudian memberikan atau menentukan hukumnya. Hal senada di
sebutkan oleh Paton, “the task of the court in actual litigation 1.1 to
discover the facts of the case, to declare the rule Qflaw that is
applicable, and then make a specific order which is the result of the
69 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Kualitas Putusan Pengadilan Niaga, Jurnal Hukum Bisnis,
Volume 22 No. 4 Tahun 2003, hlm. 25.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
39
application of the law to such facts as are considered relevant. ”70
Bahkan demi terciptanya keadilan, hakim dapat bertindak contra
legem. Contra Legem merupakan putusan Hakim pengadilan yang
mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada,
sehingga Hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau
bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal
Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan
rasa keadilan masyarakat71
Pada peradilan perdata, tugas hakim adalah mempertahankan
tata hukum perdata, dan menetapkan apa yang telah ditentukan oleh
hukum dalam suatu perkara perdata.72
Hukum acara perdata
merupakan pegangan pokok atau aturan permainan sehari-hari bagi
hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan pekara perdata
di pengadilan. Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara, menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis tidak
selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, mengingat
kodifikasi undang-undang meskipun tampak lengkap tetapi tidak
pernah sempurna. Sebab ribuan permasalahan yang tidak terduga
akan diajukan kepada hakim.73
Maka seringkali hakim harus
menemukan sendiri hukum itu (rechtsvinding), untuk melengkapi
hukum yang sudah ada, dalam menyelesaikan perkara konkrit yang
dihadapkan kepadanya, untuk dijadikan dasar dalam memutus suatu
perkara. Hakim atas inisiatif sendiri harus menggali dan menemukan
hukum dalam masyarakat.
Sudikno Mertokusumo bependapat bahwa kurangnya
pengetahuan hakim tentang hukum acara pada umumnya atau hukum
70
George W. Paton, A Text Book of Jurispudence, Clarendon Press, Oxfod, , 1975, hlm. 155. 71
Suyadi, Kemungkinan Kontra Legem dalam Pembagian Harta Bersama ( terhadap Pasal 97 KHI
)”, Makalah disampaikan untuk artikel Badilag, dibuat di Tulungangung, 31 Juli 2012. 72
R. Soepomo, Hukum Acara Pedata ( Cetakan Keenambelas), Pradnya Paramita, Jakarta, 2006,
hlm. 13. 73 Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, Bab-Bab Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta,
1993, hlm. 10
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
40
acara perdata khususnya merupakan satu faktor penghambat jalannya
peradilan.74
Di samping itu, hukum acara perdata dapat berfungsi
sebagai alat untuk memberi perlindungan kepada para pencari
keadilan, seperti yang dikemukakan oleh Fauzan:75
“ jika hakim dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai
dengan hukum acara perdata, maka hakim akan terhindar dari
tindakan sewenang-wenang dalam mengendalikan dan
melaksanakan persidangan, karena pada dasarnya hukum acara
perdata ingin melindungi pencari keadilan dengan menempatkan
kedua belah pihak sama di hadapan hukum.”
Berdasarkan bunyi Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman, pengadilan perdata, memeriksa, mengadili dan
memutus perkara yang diajukan kepadanya harus dengan sekurang-
kurangnya tiga orang hakim, yang terdiri dari seorang hakim ketua
dan yang lainnya sebagai hakim anggota dan dibantu oleh seorang
panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan
panitera kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dilihat dari
tata letak atau susunan persidangan, maka pemeriksaan perkara
perdata mensyaratkan agar kedua belah pihak duduk saling
berhadapan , yaitu antara penguggat dengan tergugat. Dalam judul
gugatan, penggugat dan tergugat saling dilawankan yang dikenal
dengan sistem adversari (adversary system). Berbeda dengan
perkara pidana yang sifatnya aquisiator di mana terdakwa tidak
duduk saling berhadapan dengan jaksa penuntut umum. 76
Sistem adversari yang dikenal dalam perkara perdata ini
disebabkan karena dalam perkara perdata kedudukan para pihak
yang berperkara adalah sama, sehingga dalam beracara di
persidangan, para pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam
74
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Ketujuh), Liberty,
Yogyakarta, 2006, hlm. 6, 75
Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’yah di Indonesia
(Edisi Pertama), Kencana Penada Media, Jakarta, 2007, hlm. viii. 76
Elisabeth Nurhaini Butarbutar , Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata, Mimbar
Hukum Volume 21, Nomor 2, Juni 2009, hlm. 364.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
41
proses jawab menjawab dan dalam proses pemeriksaan alat-alat
bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesempatan yang sama ini
juga berkaitan dengan kesempatan untuk dimenangkan dalam
perkara bergantung kepada pembuktian terhadap dalil-dalil yang
dikemukakan para pihak. Dalam perkara pidana yang
berkepentingan adalah penuntut umum sehingga yang harus
membuktikan adalah Jaksa Penuntut Umum.
Asas sidang terbuka untuk umum yang diterapkan di
Indonesia juga diterapkan di Amerika Serikat. Leonidas Ralp
Mecham dalam bukunya menyampaikan sebagai berikut.
“With certain very limited exceptions, each step of the federal
judicial process is open to the public. Federal courthouses are
designed to inspire in the public a respect for the tradition and
purpose of the American judicial process, and many courthouses
are historic buildings.
A citizen who wishes to observe a court in session may go
to a federal courthouse, check the court calendar, which is posted
on a bulletin board or television monitor, and watch any
proceeding. Anyone may review the file and papers in a case by
going to the clerk of court’s office and asking to review or copy the
appropriate case file.”77
2. Kompetensi Absolut Peradilan Agama.
a. Kompetensi dan Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia.
Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama merupakan peristiwa penting bukan hanya bagi
pembangunan hukum nasional akan tetapi juga bagi umat Islam di
Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, dengan disahkannya undang-
undang yang mengatur eksistensi peradilan agama, maka semakin
kokohlah kedudukan peradilan agama sebagai salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mandiri dalam menegakkan
hukum Islam yang pada saat itu hanya berwenang untuk menangani
perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf
77
Leonidas Ralp Mecham, The Federal Court System in United States, Administrative Office of
the US Court, Washington, 2001, hlm. 11.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
42
dan sadaqah. Selain itu, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 19 Desember 1989
tersebut membuat perubahan penting dan mendasar telah terjadi dalam
lingkungan Peradilan Agama antara lain sebagai berikut:78
1) Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya
benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum,
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2) Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acara
Peradilan Agama telah sama dan seragam di seluruh Indonesia.
Terciptanya unifikasi Hukum Acara Peradilan Agama itu akan
memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum
yangberintikan keadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
3) Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan, dengan jalan,
antara lain, memberikan hak yang sama kepada isteri dalam
berproses dan membela kepentingannya di muka Pengadilan
Agama
4) Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah
hukum Islam melalui jurisprudensi sebagai salah satu bahan baku
dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional. Disamping itu
dengan disahkannya Undang-undang Peradilan Agama ini.
5) Terlaksanalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok
Kekuasaan Kehakiman, terutama yang disebut pada Pasal 10 ayat
(1) mengenai kedudukan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Agama dan Pasal 12 tentang susunan, kekuasaan dan (hukum)
acaranya.
6) Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan
nusantara sekaligus berwawasan bhinneka tunggal ika dalam
bentuk Undang-Undang Peradilan Agama.
78
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan), Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 77-278.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
43
Kompetensi absolut pengadilan agama diatur pada Bab III UU No.
7/1989 dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa pengadilan agama
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) wakaf dan shadaqah. Dalam
Penjelasan Undang-undang Peradilan Agama ini, Pasal 49 ayat (1) di
atas dinyatakan cukup jelas.
Hukum acara yang dipergunakan oleh pengadilan agama diatur
dalam Bab IV Undang-undang Peradilan Agama. Bagian pertama
mengatur hal-hal yang bersifat umum. Di antaranya disebutkan bahwa
hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan
peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah
diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Hal yang diatur secara
khusus dalam UU No. 7/1989, disebutkan dalam bagian kedua yaitu
pemeriksaan sengketa perkawinan berkenaan dengan (a) cerai talak
yang datang dari pihak suami, (b) cerai gugat yang datang baik dari
pihak isteri maupun dari pihak suami, dan (c) cerai dengan alasan
zina.
Kemudian, pada tanggal 20 Maret tahun 2006 diundangkan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal I
angka 37 dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 49 (Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang 1) perkawinan, 2) waris, 3) wasiat, 4)
hibah, 5) wakaf, 6) zakat, 7) infak, 8) Sedekah; dan 9) ekonomi syari’ah.
Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bidang ekonomi
syariah merupakan kewenangan baru di Pengadilan Agama. Pada
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
44
penjelasan Pasal I angka 37 huruf i. dijelaskan bahwa “yang dimaksud
dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang
dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi : 1) bank
syariah, 2) lembaga keuangan mikrosyariah, 3) asuransi syariah, 4)
reasuransi syariah, 5) reksadana syariah, 6) obligasi syariah dan surat
berharga berjangka menengah syariah, 7) sekuritas syariah, 8)
pembiayaan syariah, 9) pegadaian syariah, 10) dana pensiun lembaga
keuangan syariah; dan 11) bisnis syariah.
Selain penambahan kewenangan absolut, asas personalitas
keIslaman pada peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengalami ekstensi
makna. Maksud yang yang dikandung dalam asas ini semakin meluas
menjadi seperti berikut:79
1) Pihak-pihak yang bersengketa beragama Islam.
2) Pihak-pihak yang bersengketa juga termasuk orang atau badan
hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela
kepada hukum Islam.
3) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan pihak-pihak
tersebut berdasarkan hukum Islam.
4) Perkara-perkara yang disengketakan terbatas pada bidang
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan
ekonomi syariah
b. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama di Indonesia.
Eksistensi pengadilan agama di Indonesia berikut dengan
kewenangan mengadili perkara-perkaranya tidak bisa dilepaskan dari
pendekatan sejarah tentang keberlakuan hukum Islam di Indonesia.
Ketika orang Belanda sampai di Nusantara abad ke 16 dan 17 Masehi,
mereka menemukan beberapa kerajaan besar atau kecil yang tersebar
di berbagai pelosok, terutama kerajaan-kerjaan Islam di wilayah
79
Abd. Shomad, Op.Cit., hlm. 209-210
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
45
pesisir.80
Sebuah negara bagaimanapun kecilnya pasti diatur
berdasarkan hukum tertentu, tidak terkecuali keadaan Indonesia pada
masa itu, dan sebuah kenyataan pula bahwa mayoritas penduduk
nusantara beragama Islam.
Berdasarkan kenyataan ini maka beranjak dari teori receptio in
complexu81
yang diramu oleh L.W.C. van den Berg, pemerintah
jajahan Belanda menyatakan bahwa hukum Islam tanpa membedakan
apakah mereka merupakan muslim yang taat atau bukan.
Kebijakan pemberlakuan hukum Islam kepada ummat Islam ini
masih diperhatikan oleh pemerintah jajahan sampai kemudian
80
Kerajaan-kerajaan Islam muncul di beberapa daerah di Nusantara. Di Sumatera muncul
kerajaan diantaranya: Samudra Pasai, Perlak, Siak Sriindrapura, Pidie, Aceh, Jambi, Deli
Serdang, Langkat, Tanjungpura. Di Jawa seperti di Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, dan
Banten. Di Madura di Arosbaya, Bangkalan, Sampang, dan Sumenep, sedang di Kalimantan
muncul Kerajaan Banjar dan Kutai. Di Sulawesi muncul kerajaan Gowa Tallo, Bone, Luwu
dan Sindereng, Wajo dan Sopeng. Di Maluku Kerajaan Ternate, Tidore, Hitu, Jailol, dan
Bacan, sedang di Nusa Tenggara muncul kerajaan Bima.
Lihat : Sjamsudduha, Penyebaran dan Perkembangan Islam Katholik-Protestan di Indonesia,
Usaha Nasional,. Surabaya, 1987, hlm. 34-35 dalam Abd. Shomad, ibid.
Pengadilan agama pada tingkat pertama dan tingkat banding yang ada pada sekarang ini,
dahulu memiliki nama yang berbeda-beda, antara lain Pengadilan Agama, Mahkamah
Syar’iyah, Kerapakatan Qadi, Mahkamah Islam Tinggi, Mahkamah Syar’iah Propinsi dan
Kerapatan Qadi Besar. Untuk penyatuan nama yang berbeda-beda itu, dengan Surat Keputusan
Menteri Agama No. 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980, dilakukan penyeragaman nama-
nama tersebut. Dengan demikian, Kerapatan Qadi di Kalimantan Selatan dan sebagian
Kalimantan Timur, Mahkamah Syari’ah di Luar Jawa dan Madura, Kalimantan Selatan dan
Timur itu, disebut Pengadilan Agama, suatu nama yang sudah terkenal dalam lingkungan
peradilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama di Jawa dan Madura. Mahkamah Syari’ah
Propinsi dan Kerapatan Qadi Besar, diseragamkan pula namanya dengan Pengadilan Tinggi
Agama, nama baru sebagai pengganti nama Mahkamah Islam Tinggi yang berfungsi sebagai
pengadilan banding atas perkara-perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama, seperti
yang terdapat di Jawa.
Lihat: Mohammad Daud Ali, Op.Cit. hlm. 224-225 81 Teori Receptio in Complexu ini menyatakan bahwa selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan,
hukum pribumi ikut agama, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukumhukum
agama itu dengan setia. Jika suatu masyarakat memeluk suatu agama tertentu, maka hukum
adat masyarakat itu adalah hukum agama yang dipeluknya. Iika ada hal-hal yang menyimpang,
maka dianggap sebagai perkecualian atau penyimpangan dari hukum agama yang telah
ditemukan dalam keseluruhan. Cikal bakal teori ini dari pendapat Solomon Keyzer dan
didukung oleh LWC Van den Berg. Lihat : Sayuti Thalib, Receptio a Contrario, Hubungan
Hukum Adat dan Hukum Islam, Academica, Jakarta, 1980 dalam Abd. Shomad, ibid, hlm. 211.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
46
Christian Snouck Hurgronje82
memperkenalkan istilah adat recht
(hukum adat) pada tahun 1983. Dari penelitiannya di Aceh, Snouck
berkesimpulan bahwa hukum Islam yang diberlakukan di Aceh
tidaklah hukum Islam murni, akan tetapi hukum Islam yang telah
diterima oleh hukum Adat. Dari sini kemudian ia terkenal dengan
teori receptie yang ia kemukakan bahwa hukum Islam yang dapat
diberlakukan oleh pemerintah hanyalah hukum Islam yang telah
diresepsi oleh hukum adat setempat.83
Teori receptie mendapat tanggapan serius dari Hazairin84
yang
menyatakan bahwa teori Snouck bersifat tendensius dengan maksud
82 Christian Snouck Hengronje, lahir pada tahun 1857 dan meninggal tahun 1936, adalah seorang
ahli bahasa, seorang doktor bahasa-bahasa timur dan Islam, pernah menjabat sebagai Adviseur
voor Arabische-en Islamitische Zaken, menggabungkan studi bahasa Arab dan Islam dengan
tekanan khusus pada Hukum Islam di satu pihak dengan perhatiannya pada Islam kontemporer
di Hindia Belanda, atau dalam arti luas, linguistik dan, antropologi Hindia Belanda bahkan
politik kolonialisme. Dia memasuki Makkah dengan nama samaran Abdul Gaffar untuk
mempelajari agama Islam pada tahun 1884-1885, dengan menyamar sebagai dokter mata dan
tukang potret. Pada saat belajar Islam di Makkah banyak bergaul dengan orang Jawa terutama
di sebuah Hotel Aceh di pusat kota Mekkah, yang membawa pada pengenalan tentang lembaga
hukum adat di Indonesia. Sesudah diusir dari Makkah kemudian ditempatkan di Hindia
Belanda. Dan berkeliling Pulau Jawa selama tahun 1889-1891 untuk mengumpulkan bahan-
bahan mengenai pendidikan agama Islam di Jawa, dan juga mendapatkan bahan-bahan tentang
hukum adat. Pada tahun 1875 muncul pemberontakan Aceh yang menyebabkan Christian
Snouck Hurgronje pada tahun 1889 diangkat menjad' kepala kantor yang baru didirikan, kantor
Penasihat Urusan Arab dan Islam (Adviseur voor Arabische-en Islamitische Zaken) hingga
tahun 1906, dan sekalipun ia telah kembali ke negeri Belanda ia tetap masih menjadi penasihat.
Lihat : Abd. Shomad, ibid. hlm. 214, 83
John Ball mengemukakan pendapat bahwa apa yang dimaksud hukum Adat tidak memiliki
makna tunggal. Ia kadang-kadang dimaksudkan sebagai “the native customs and uses” ( adat
istiadat dan kebiasaan asli), atau “ the religious law, institutions and customs” (adat istiadat,
kelembagaan dan hukum-hukum keagamaan), “the religious laws or customs” ( hukum-hukum
keagamaan dan adat istiadat) dan lain-lain.
Lihat : John Ball, Indonesian Law at the Crossroad: Commentary and Materials, Oughtershaw
Press, Sydney, 1996, hlm. 1,3.
Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum Adat yang dimaksud adalah hukum lokal
Nusantara yang dipengaruhi oleh berbagai unsur yang diberlakukan oleh penduduk bumi
putera sewaktu Belanda sampai di Indonesia. 84 Teori ini dikritik Hazairin dengan teori receptie exit, maksudnya adalah bahwa teori receptie
harus keluar dari teori hukum nasional Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945 serta
bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pada tahun 1950 dalam Konferensi
Departemen Kehakiman di Salatiga, Hazairin, mengarahkan suatu analisa dan pandangan agar
hukum Islam itu berlaku di Indonesia, tidak berdasar pada hukum adat. Berlakunya hukum
Islam untuk orang Indonesia supaya disandarkan pada penunjukan peraturan perundang-
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
47
menelantarkan hukum Islam yang sudah berlaku di kalangan
penduduk pada masa itu. Sebagai seorang islamolog, Snouck tahu
betul tentang posisi hukum Adat dalam konteks hukum Islam, tetapi ia
sengaja menggunakan pengertian baru sama sekali untuk mengalihkan
perhatian dari hukum Islam yang diyakini oleh mayoritas penduduk.
Karena itu, Hazairin sering menyebut teori receptie adalah teori iblis,
yaitu makhluk halus iblis yang mempunyai tabiat menyesatkan
manusia dengan tipu muslihatnya.85
Hazairin cukup beralasan karena
Snouck Hurgronje sebenarnya adalah seorang ateis yang pernah
menjadi intel Belanda dan menyamar sebagai seorang muslim di
Makkah dengan nama ‘Abdul Ghafar.86
Teori hukum Adat selanjutnya dikembangkan oleh Cornelis van
Vollenhoven yang membagi wilayah Nusantara kepada beberapa
wilayah Nusantara kepada beberapa wilayah hukum Adat. Ia telah
berusaha keras mengkodifikasi hukum Adat dari berbagai wilayah di
Indonesia dengan maksud akan menjadikannya sebagai hukum
penduduk bumi putera, tetapi bahkan sampai ke masa pendudukan
Jepang pada tahun 1942, upaya ini tidak pernah berhasil karena tidak
mendapatkan dukungan penuh pemerintahan jajahan.87
Sungguhpun
undangan sendiri. Sama seperti hukum adat selama ini yang dasar memperlakukan hukum adat
itu sendiri ialah berdasarkan sokongan peraturan perundang-undangan. Dalam bukunya tentang
Hukum Kekeluargaan Nasional, Hazairin berpandangan bahwa teori receptie Christian Snouck
Hurgronje itu sebagai teori iblis. Ungkapan Hazairin ditujukan pula kepada tidak sahnya lagi
Pasal 134 (2) IS, dijadikan dasar pengaturan hukum di Indonesia. Kritik lain diantaranya
dilakukan Sayuti Thalib melalui teori yang disebutnya Teori Receptio a Contrario-nya.
Lihat: Abd. Shomad, ibid, hlm. 218. 85
Hazairin, Demokrasi Pancasila, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 97 86
P.S.J. Van Koningsveld, Snouck Hurgronje dan Islam, terjemahan dari Acht artkelen over
leven en werk van een orientalist uit het koloniale tijdperk, Grimukti Pustaka, Jakarta, 1989
dalam Rifyal Ka’bah, Peradilan Islam Kontemporer: Saudi Arabia, Mesir, Sudan, Pakistan,
Malaysia dan Indonesia, Universitas Yarsi, Jakarta, 2009, hlm. 113 87
Peter Burns dalam disertasinya mengupas secara luas tentang upaya Van Vallenhoven
memperjuangkan teorinya, yang oleh Burns disebut sebagai “The Leiden Legacy”. Ia antara
lain menyimpulkan : “The body of Von Vollenhoven, like that John Brown, may lie . . . a
moldering in the grave, but his influence, like the soul of the slave-saving rebel, still marches
on... ( despite his great personal values), Van Vallenhoven marches – as his latter day
followers still march – steadly and with great confidence, in a wrong direction.” ( Mayat Van
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
48
demikian, Van Vallenhoven, Ter Haar dan para penganjur hukum
hukum Adat yang lain dari kalangan bangsa Belanda mempunyai
murid-murid sampai ke zaman kemerdekaan dari kalangan orang-
orang Indonesia sendiri, dan sampai sekarang, hukum Adat masih
tetap dipandang sebagai salah satu unsur hukum nasional Indonesia.
Ini di samping unsur-unsur lain yang terdiri dari hukum Islam dan
hukum warisan kolonial Belanda. Malah di zaman kemerdekaan,
unsur-unsur hukum Indonesia tidak hanya terdiri dari perundang-
undangan warisan kolonial, hukum Islam dan hukum Adat, tetapi juga
perundang-undangan yang mengambil aspirasi dari perundang-
undangan Barat modern, terutama bidang hukum ekonomi dan HAM.
Sejarah tentang pembentukan pengadilan agama di Indonesia,
Mohammad Daud Ali menulis bahwa selain pemikiran dari LWC van
den Berg, pemikiran Scholten van Oud Haarlem yang menjadi Ketua
Komisi Penyesuaian Undang-Undang (kodifikasi hukum) Belanda
dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda sekitar pertengahan abad
XIX (1828) juga mempengaruhi lahirnya Pengadilan Agama dan
penentuan wewenang lainnya pada masa tersebut. Menurut pendapat
Paul Scholten, “Untuk mencegah perlawanan dari ummat Islam,
karena hukum anak negeri dan agama Islam dilanggar, haruslah
diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar orang-orang pribumi yang
beragama Islam dapat tetap tinggal di lingkungan hukum agama dan
adat istiadat mereka”.
Pendapat van den Berg dan Paul Scholten yang didasarkan pada
kenyataan yang ada dan yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat bumiputera yang beragama Islam itulah yang mendorong
Vallenhoven adalah seperti mayat John Brown, barangkali terbaring ... hancur luluh di
kuburan, tetapi pengaruhnya adalah seperti pemberontak penyelamat budak masih
bergentayangan ... ( di samping nilai pribadinya yang agung). Van Vallenhoven
bergentayangan, seperti juga para pengikut terakhirnyta masih bergentayangan, dengan
tangguh dan percaya diri yang besar, dalam sebuah arah yang salah).
Lihat: Peter Burns, The Leiden Legacy: Concept of Law in Indonesia, KITLV Press, Leiden,
2004, hlm. 253.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
49
lahirnya Staatsblad 1882:152 yang memuat penetapan raja Belanda
tentang priesterrad atau raad agama atau pengadilan agama di Jawa
dan Madura. Karena dalam S. 1882: 152 itu tidak disebutkan dengan
jelas wewenang pengadilan agama, maka pengadilan agama itu sendiri
yang menetapkan perkara-perkara yang dipandangnya masuk ke
dalam lingkungan kekuasaannya yakni perkara-perkara yang
berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian, mahar,
nafkah, sah tidaknya anak, perwalian, kewarisan, hibah, sadaqah,
baitulmal dan waqaf. Dengan kata lain, pengadilan, yang menjadi
wewenang Pengadilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal yang
berhubungan dengan hukum perkawinan dan hukum kewarisan dan
wakaf. Penentuan wewenang ini adalah kelanjutan praktek peradilan
dalam masyarakat bumiputera yang beragama Islam sejak zaman
kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya yang dilanjutkan terus di zaman
VOC. Dalam hubungan ini, dapat dikemukakan bahwa, menurut
perkiraan, peradilan agama (dalam bentuknya yang sederhana) telah
ada di Indonesia sejak agama Islam masuk dan membentuk
masyarakat Islam di Nusantara. Dilihat dari sudut pandang ini, S.
1882:152 yang mengatur pengadilan agama di Jawa dan Madura itu
sesungguhnya adalah pengakuan resmi dan pengukuhan sesuatu yang
telah ada dalam masyarakat. Ini berarti pula bahwa Pengadilan agama
pada waktu itu sengaja didirikan, untuk memenuhi kebutuhan hukum
orang Indonesia yang beragama Islam.88
Teori resepsi yang berusaha menyingkirkan eksistensi hukum
Islam dari kehidupan hukum orang Islam Indonesia, ketika Regerings
Reglement (RR) tahun 1854 diubah menjadi Indische Staatsregeling
(IS) atau Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda pada tahun 1925,
dimasukkan ke dalam “Undang-Undang Dasar Hindia Belanda” itu
dan dicantumkan dalam Pasal 134 ayat (2). Isi Pasal 134:2 IS ini ini
kemudian ditampung oleh S. 1937 No. 116 yang berisi peraturan yang
88
Mohammad Daud Ali, Op.Cit, hlm. 226-227
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
50
mencabut wewenang Pengadilan Agama mengadili perkara warisan di
Jawa dan Madura. Mengenai lembaga pengadilan agamanya sendiri,
karena sudah terlanjur terbentuk, Snouck Hurgronje menasihatkan
kepada pemerintahnya agar dibiarkan saja berjalan sendiri, dengan
harapan kalau tidak kuat lagi akan berhenti dan mati.
Karena pengaruh teori dan penganut teori resepsi, pada tahun 1922,
pemerintah (Hindia) Belanda membentuk komisi yang bertugas
meninjau kembali kewenangan Raad atau pengadilan agama yang
didirikan tahun 1882 tersebut dalam hal kewenangan mengadili
perkara kewarisan menurut hukum Islam. Komisi yang dikuasai oleh
ter Haar, penganut berat teori resepsi, menyarankan kepada
pemerintah (Hindia) Belanda untuk meninjau kembali wewenang
Pengadilan Agama dengan membatasinya pada bagian-bagian hukum
Islam yang benar-benar telah diterima oleh dan menjadi hukum adat.
Oleh karena hanya hukum perkawinan Islam yang dianggap telah
diterima oleh hukum adat, maka wewenang pengadilan agama
hanyalah mengenai dan di sekitar hukum perkawinan saja. Karena
hukum kewarisan dipandang belum merupakan kenyataan hukum
dalam masyarakat bumiputra yang beragama Islam di Jawa dan
Madura, melalui S. 1937 No. 116 tersebut diatas dinyatakan bahwa
Pengadilan Agama tidak berwenang lagi mengadili perkara kewarisan
menurut hukum Islam. Kemudian sejak 1 April 1937 beralihnya
wewenang mengadili perkara kewarisan menurut hukum Islam dari
Raad Agama atau Pengadilan Agama ke Landraad atau Pengadilan
Negeri yang memeriksan dan memutus perkara kewarisan menurut
hukum adat (setempat). Sejak itu, pada masa itu wewenang
pengadilan agama di Jawa dan Madura hanyalah mengenai soal
perkawinan dan perceraian saja.
Walaupun secara resmi pengadilan agama telah kehilangan
kekuasaannya atas perkara kewarisan sejak tahun 1972, namun
demikian, menurut Daniel S. Lev, Pengadilan Agama di Jawa masih
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
51
tetap menyelesaikan perkara-perkara kewarisan dengan cara-cara yang
sangat mengesankan. Dalam kenyataannya, banyak pengadilan agama
menyisihkan satu atau dua hari dalam seminggu khusus untuk
menerima masalah-masalah kewarisan. Di beberapa daerah,
pengadilan agama bahkan menerima perkara kewarisan lebih banyak
dari pengadilan negeri. Sementara itu, perlu ditambahkan pula bahwa
sudah sejak lama (di Jawa) fatwa waris Pengadilan Agama diterima
oleh notaris dan para hakim Pengadilan Negeri sebagai alat bukti sah
sebagai hak milik dan tuntutan berkenaan dengan hak milik itu.
Demikian pula dengan pejabat pendaftaran tanah di Kantor Agraria.
Rifyal Ka’bah berpendapat bahwa dari sudut politik hukum Islam,
di Indonesia terdapat dua kecenderungan dari awal kemerdekaan
sampai sekarang di kalangan ahli hukum, terutama hukum Islam.
Kecenderungan pertama adalah hukum Islam berlaku untuk warga
yang beragama Islam, dan kecenderungan kedua adalah bahwa
substansi hukum Islam masuk ke dalam perundang-undangan
Indonesia tanpa label Islam sehingga mengikat kepada semua warga
negara tanpa melihat agamanya. Misalnya substansi hukum pidana,
perdata dan ekonomi Islam menjadi bagian yang integral dari hukum
pidana, perdata dan ekonomi Islam menjadi bagian yang integral dari
hukum pidana, perdata dan ekonomi nasional Indonesia tanpa
menyatakan bahwa substansi ini sebagai substansi hukum Islam.
Kedua kecenderungan ini mengemuka dalam perkembangan hukum
Islam di Indonesia sejak awal proklamasi kemerdekaan sampai
sekarang.89
89
Pendekatan seperti ini antara lain didukung oleh Padmo Wahjono. Beliau antara lain
menyatakan: “ Memasukkan budaya hukum Islam, maka kita dihadapkan kepada dua
kemungkinan : (a) mengenai hukum positif Islam, sehingga kita terbatas memasalahkan hukum
yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam, atau (b) mengenai nilai-nilai hukum Islam,
yang akan dapat berlaku bagi seluruh warga negara, bahkan mungkin seluruh penduduk
termasuk yang bukan warga negara. Kedua alternatif ini dapat mempengaruhi pembentukan
hukum nasional di masa yang akan datang.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
52
Istilah syariah masuk pertama kali ke dalam khazanah hukum
Indonesia melalui UU No. Tahun 1998, Undang-Undang yang
merevisi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di mana diyatakan
dalam Pasal 1 ayat (12) tentang pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah. Dalam pasal ini diterangkan dengan jelas bahwa yang
dimaksud prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum
Islam. Jadi istilah syariah disini disamakan dengan hukum Islam.
Istilah syariat juga muncul dalam Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) UU
No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh
sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal ini mengatur
tentang Peradilan Syariat Islam dengan nama Mahkamah Syariyah
dengan kewenangan berdasarkan Syariat Islam dalam sistem hukum
nasional yang diatur secara khusus dengan Qanun Aceh sebagai Perda
(Peraturan Daerah) khusus otonomi Aceh.
Mahkamah Syariah atau Peradilan Syariat Islam di Propinsi NAD
adalah Pengadilan Agama plus dengan kewenangan melebihi
pengadilan agama di propinsi-propinsi lain berdasarkan Qanun. Di
propinsi-propinsi lain, kewenangan pengadilan agama terbatas dalam
tujuh bidang seperti diatur dalam Pasal 49 UU No. 3/2006 jo. 50/2009,
tetapi sesuai UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, di
Aceh meliputi bidang yang luas sekali, yaitu ibadah, hukum keluarga
(al-ahwal ash-shakhsiyyah), hukum perdata (al-mu’amalah), hukum
pidana (al-jinayah), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan),
dakwah, syiar dan pembelaan Islam, yang akan diterapkan
berdasarkan Qanun (Pasal 125 ayat 1, 2 dan 3). Dengan berlakunya
Undang-Undang tersebut, pengertian Syariat Islam di Aceh kembali
kepada makna asalnya, yaitu sebagai agama Islam itu sendiri atau
sebagai the right way of religion menurut pemahaman Abdullah Yusuf
Lihat : “Padmo Wahjono,”Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di
Masa Datang”, dalam Amrullah Ahmad et. al. (eds), Prospek Hukum Islam dalam Kerangka
Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama,
Jakarta, 1994, hlm. 241.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
53
Ali.90
Syariat dengan pengertian luas seperti ini tidak hanya
menyangkut aspek hukum dari agama Islam, sebagai fiqh dalam
pengertian yang lazim, tetapi keseluruhan agama Islam.
Kembali kepada kompetensi absolut pengadilan agama, Pasal 49
Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 51 Tahun 2009 , menyatakan bahwa salah satu kewenangan
peradilan agama adalah memutus sengketa dalam bidang ekonomi
syariah. Hukum ekonomi syariah dimaksud meliputi sebelas jenis,
yaitu a. bank syariah; b. lembaga keuangan makro syariah; c. asuransi
syariah; d. reasuransi syariah; e. reksadana syariah; f. obligasi syariah
dan surat berharga berjangka menengan syariah; g. sekuritas syariah,
h. pembiayaan syariah; i. pegadaian syariah; j. Dana pensiun lembaga
keuangan syariah; dan k. Bisnis syariah. Dengan kesebelas jenis
hukum ekonomi syariah ini berarti hampir seluruh cakupan fiqih
mu’amalat dalam syariat Islam telah menjadi hukum positif di
Indonesia.
3. Tinjauan tentang Kepailitan dan Pengadilan Niaga.
a. Definisi Kepailitan.
Berdasarkan tata bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal
yang berhubungan dengan pailit,91
sedangkan secara etimologi, istilah
kepailitan berasal dari kata “pailit”.92
Istilah “pailit” juga ada dalam
perbendaharaan bahasa Belanda, Prancis, Latin, dan Inggris namun
dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Belanda, pailit
berasal dari istilah “failiet” yang mempunyai arti ganda, yaitu selain
sebagai kata benda, juga sebagai kata sifat. Dalam bahasa Prancis,
90
Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur’an: Text, Translation and Commentary, Amana
Corporation, Maryland, 1409/1989 hlm. 1297 91
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Kepailitan, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2000, hlm. 11 92
Victor Situmorang dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka
Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 18.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
54
pailit berasal dari kata “faillite” yang berarti pemogokan atau
kemacetan melakukan pembayaran, sehingga orang yang mogok atau
berhenti membayar utangnya dalam bahasa Prancis dinamakan “le
failit”,93
dalam bahasa Inggris diterjemahkan “failure” yang berarti
gagal, dan dalam bahasa Latin disebut “fallire”94
Pada negara–negara
yang menggunakan bahasa Inggris, pengertian pailit mempergunakan
istilah "bankrupt" atau "bankruptcy", yang dalam Black’s Law
Dictionary memiliki pengertian sebagai:95
.
"The state or condition of a person (individual, partnership,
corporation, municipality) who is unable to pay its debts as they are,
or became, due". The term includes a person against whom an
involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary
petition, or who has been adjudged a bankrupt."96
Black’s Law Dictionary tersebut, menjelaskan pailit sebagai
ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-
utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus
disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang
dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri maupun atas permintaan
pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke
pengadilan.97
Sedangkan dalam kamus umum bahasa Indonesia,
“pailit” artinya “bangkrut” dan “bangkrut” artinya menderita kerugian
besar hingga jatuh (perusahaan, toko dan sebagainya). Secara normatif,
pengertian kepailitan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Kepailitan menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua
kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan 93
Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, Hak Kreditur Separatis Dalam Mengeksekusi
Benda Jaminan Debitur Pailit, LaksBang, Yogyakarta, 2011, hlm. 63 94
Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1994, hlm. 28 95
Siti Soemaryati Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Liberti,
Yogyakarta, 1981, hlm. 4. Lihat juga Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di
Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 11 96
Henry Campbell Black, Op. Cit., hlm. 100 97
Kartini Mulyadi, Hukum Kepailitan, Putra Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 143.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
55
oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana
diatur dalam undang-undang ini.
Dalam hal debitur tidak membayar utang yang jatuh tempo, maka
perlu ada mekanisme yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan
efektif. Pada posisi ini, lembaga kepailitan berfungsi sehingga dapat
memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan debitur untuk
mengupayakan penyelesaian secara adil,98
yaitu perangkat hukum
yang melindungi kepentingan kreditur untuk mendapatkan kembali
hak-haknya sekaligus melindungi debitur dari cara-cara penyelesaian
yang tidak wajar dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Demikian pula, Sri
Redjeki Hartono menyampaikan bahwa Lembaga Kepailitan
memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam
keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga
Kepailitan mencegah atau menghindari dua hal berikut, yang
keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat
merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi massal oleh
debitur atau kreditur dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitur
sendiri.99
.
Sesungguhnya KUHPerdata juga telah mengatur perihal kepailitan,
yaitu dalam ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal
1131 KUHPerdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang,
baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun
yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala
perikatan perseorangan, dan Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan
bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua
orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-
benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar
98
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op.Cit., hlm. 2. 99
Sri Redjeki Hartono, Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, Jurnal Hukum
Bisnis Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hlm. 22
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
56
kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para
berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Kedua
Pasal tersebut pada dasarnya telah mengatur tentang pemberian
jaminan kepastian kepada kreditur bahwa debitur berkomitmen untuk
tetap memenuhi kewajibannya, dan komitmen tersebut dijamin dengan
kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada
di kemudian hari. Pasal 1131 KUHPerdata mengandung asas bahwa
setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab
mana berupa menyediakan kekayaannya baik benda bergerak maupun
benda tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya
(asas schuld dan haftung),100
sedangkan Pasal 1132 KUHPerdata
mengandung asas bahwa dengan demikian setiap kreditur memiliki
kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya (asas paritas
creditorum), kecuali ditentukan undang-undang karena memiliki
alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur
lainnya.101
Sudut pandang sejarah menyatakan bahwa hukum kepailitan yang
semula berlaku di Indonesia adalah Faillissement Verordening atau
Peraturan Kepailitan yang termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 No.
217 juncto Staatsblad Tahun 1906 No.348. Pada saat terjadi krisis
moneter pada tanggal 22 April 1998, Pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
tentang Kepailitan atau Peraturan Kepailitan (selanjutnya disebut
Perpu PK) yang mulai berlaku tanggal 20 Agustus 1998, yaitu 120
hari sejak diundangkan. Kemudian pada tanggal 9 September 1998,
Perpu PK tersebut ditetapkan menjadi undang-undang melalui
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang
100
Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT, Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 5. 101
Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 2000,
hlm. 32.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
57
Penetapan Perpu No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, yang mana
dalam ketentuan Pasal 1 bagian akhir dari undang-undang ini,
dinyatakan bahwa Perpu PK selanjutnya dilampirkan dan menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini dan disebut
sebagai Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya, pada tanggal 18
Oktober 2004 Indonesia telah memiliki perangkat hukum terbaru
dibidang kepailitan yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dinyatakan mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.
b. Konsep Kepailitan.
Konsep kepailitan didasari pada satu hal utama yang menjadi
pokok dapat terjadinya kepailitan yaitu mengenai utang. Tanpa
adanya utang, maka kepailitan akan kehilangan esensinya sebagai
pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitur guna
membayar utang-utangnya kepada para krediturnya.102
Secara umum dapat diklasifikasikan konsep dasar kepailitan
sebagai berikut:103
1) Debt collection.
Debt collection merupakan konsep pembalasan dari kreditur
terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap
debitur atau harta debitur.
2) Debt forgiveness.
Debt forgiveness dimanifestasikan dalam bentuk asset exemption
(beberapa harta debitur dikecualikan terhadap budel pailit), relief
from imprisonment (tidak dipenjara karena gagal membayar
102
M. Hadi Shubhan, Op.Cit, hlm. 34. 103
Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, 2005, Undang – undang Kepailitan dan Perkembangannya
: Prosidings Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – masalah Kepailitan dan Wawasan
Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004, (Cetakan 2 ), Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm.
xix.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
58
utang), moratorium (penundaan pembayaran untuk jangka waktu
tertentu), dan discharge of indebtedness (pembebasan debitur
atau harta debitur untuk membayar utang pembayaran yang
benar – benar tidak dapat dipenuhinya)
3) Debt adjusment.
Debt adjusment merupakan hak distribusi dari para kreditur
sebagai suatu grup, dengan menerapkan prinsip pro rata
distribution atau structured prorata (pembagian berdasarkan
kelas kreditur) serta reorganisasi serta Penundaan Kewajiban
Pembayaran utang (PKPU).
Dari pengklasifikasikan konsep dasar kepailitan tersebut,
maka pada dasarnya kepailitan berkenaan dengan
"ketidakmampuan untuk membayar" dari debitur atas utang-
utangnya yang jatuh tempo. Atas ketidakmampuan tersebut,
perlu dilakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit ke
pengadilan niaga, baik oleh kreditur maupun secara sukarela
oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan orang lain atau
pihak ketiga.
Warren dalam bukunya Bankruptcy Policy mengemukakan sebagai
berikut:104
“In bankruptcy, with an inadequate pie to divide and the looming
discharge of unpaid debts, the disputes center on who is entitled to
shares of the debtor’s assets and how these shares are to be divided.
Distribution among creditors is no incidental to other concerns; it is
the center of the bankruptcy scheme.”
Berkenaan dengan pendapat tersebut, Emmy Yuhassarie dan Trie
Harwono berpendapat bahwa intinya hukum kepailitan (bankruptcy
law) adalah “a debt collective system”, walaupun bankruptcy bukan
satu-satunya “debt collection system.” Sehingga tujuan kepailitan
adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua
104
Epstein et al., Bankruptcy, St. Paul, West Publishing Co., Minnesota, 1993, hlm. 2
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
59
kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.105
Hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat collective proceeding,
dalam rangka mengatasi collective action problem yang timbul dari
kepentingan masing-masing kreditur. Artinya, hukum kepailitan
memberikan suatu mekanisme bagi para kreditur agar secara bersama-
sama dapat menentukan apakah sebaiknya perusahaan atau harta
kekayaan debitur diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak, dan
dapat memaksa kreditur minoritas mengikuti skim karena adanya
prosedur pemungutan suara.
Sejalan dengan konsep kepailitan, dapat dinyatakan bahwa
beberapa tujuan dari hukum kepailitan yaitu diantaranya untuk:106
1) Melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka
sehubungan dengan berlakunya asas jaminan;
2) Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para
kreditur sesuai dengan asas pari passu;
3) Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang
dapat merugikan kepentingan para kreditur;
4) Memberikan kesempatan kepada debitur dan para krediturnya
untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai
restrukturisasi utangutang debitur.
c. Asas-Asas Hukum Kepailitan Indonesia.
Asas-asas hukum kepailitan di Indonesia terdiri dari:107
asas
keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integrasi.
Sesuai asas keseimbangan tersebut, maka Undang-Undang Kepailitan
harus mampu mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga
kepailitan baik oleh debitur yang tidak jujur maupun kreditur yang
105
Emmy Yuhassarie dan Tri Harwono, Op.Cit., h. 96 106
Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan, Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 29 – 31. 107
Rahayu Hartini, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia; Dualisme Kewenangan
Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.
75-76.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
60
tidak beriktikad baik. Adrian Sutedi menyampaikan bahwa: Undang-
Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang
bagi kreditur dan debitur, menjunjung keadilan dan memperhatikan
kepentingan keduanya, meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu
untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat,
adil, terbuka, dan efektif.108
Mengenai asas kelangsungan usaha, Undang-Undang Kepailitan
perlu mengatur agar perusahaan debitur yang prospektif
memungkinkan untuk tetap dilanjutkan. Oleh karena itu permohonan
pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan terhadap debitur
yang insolvent, yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada
para kreditur mayoritas. Berdasarkan asas keadilan, hukum kepailitan
harus memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, sehingga, putusan
pernyataan pailit seharusnya berdasarkan persetujuan para kreditur
mayoritas, dan Undang-Undang Kepailitan harus mengkriminalisasi
kecurangan menyangkut kepailitan debitur. Berdasarkan asas
integrasi, maka hukum kepailitan, baik sistem hukum formil dan
hukum materiilnya merupakan bagian yang menyatu secara utuh
dalam sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.109
d. Syarat-Syarat Permohonan Kepailitan.
Mengenai syarat-syarat pernyataan pailit, saat ini di Indonesia
masih mengikuti hukum acara yang berlaku di pengadilan niaga
adalah hukum acara perdata yang berdasarkan atas HIR/RBG, kecuali
untuk hal yang ditetapkan lain oleh Undang-Undang Kepailitan.
Pengajuan permohonan pernyataan pailit harus memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan, karena apabila syarat-syarat
tersebut tidakdipenuhi, maka permohonan pernyataan pailit tersebut
tidak dikabulkan oleh pengadilan niaga.110
108
Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 30. 109
Loc.Cit, hlm. 31 110
Loc.Cit, hlm. 52.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
61
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Kepailitan, dapat disimpulkan syarat-syarat pengajuan permohonan
pernyataan pailit adalah sebagai berikut:111
1) debitur yang diajukan harus memiliki lebih dari satu kreditur;
2) debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah
satu krediturnya
3) utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah
dapat ditagih (due and payable).
Berdasarkan syarat-syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit
tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:112
1) Memiliki Dua Kreditur
Syarat keharusan adanya minimal dua atau lebih kreditur
yang dikenal sebagai concursus creditorum, sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU dan ketentuan Pasal 1132
KUHPerdata,113
yang menentukan pembagian harta pailit kepada
para krediturnya secara teratur berdasarkan prinsip pari passu pro
rata parte. Dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan berapa besar
Piutang yang harus ditagih oleh seorang kreditur dari debitur yang
bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi
kreditur dari debitur yang bersangkutan.114
Perihal syarat
sekurangnya dua orang kreditur merupakan suatu syarat mutlak
sebab jika hanya ada satu kreditur tidak perlu kepailitan karena
tidak perlu pengaturan pembagian hasil eksekusi harta pailit
kepada beberapa kreditur.115
Apabila seorang debitur hanya
memiliki satu orang kreditur, maka eksistensi dari UUKPKPU
kehilangan raison d’être-nya, sebab apabila diperkenankan
111
Ibid, hlm. 52. 112
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 141 113
Ibid, hlm. 107 114
Rachmadi Usman, Op. Cit hlm. 15. 115
Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
62
pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang
hanya memiliki seorang kreditur, maka sesuai ketentuan Pasal
1131 KUHPerdata, tidak perlu ada pengaturan mengenai
pembagian hasil penjualan seluruh harta kekayaan debitur yang
merupakan jaminan utangnya karena seluruh hasil penjualan
tersebut merupakan sumber pelunasan bagi kreditur satu-satunya
itu, sehingga tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan
perebutan terhadap harta kekayaan debitur karena hanya ada satu
orang kreditur.116
Berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat
(1) UUKPKPU, maka yang dimaksud dengan kreditur adalah baik
kreditur konkuren, kreditur separatis dan kreditur preferen.
2) Harus Ada Utang
Syarat keadaan dimana seorang debitur berhenti membayar
atau tidak dapat membayar utang, dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-undang Kepailitan mengenai
pengertian utang. Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata,
kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau dari
undang-undang. Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk
berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.117
Syarat ini dapat diartikan sebagai keadaan di mana debitur
tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pernyataan pailit
diajukan ke pengadilan niaga, sehingga apabila debitur masih
dapat berprestasi pada saat permohonan pernyataan pailit diajukan
ke pengadilan, maka debitur yang bersangkutan belum berada
dalam keadaan berhenti membayar. Sidang pengadilan harus dapat
membuktikan berdasarkan fakta atau keadaan bahwa debitur tidak
berprestasi lagi, sehingga dirinya dikatakan berada dalam keadaan
tidak dapat membayar utang-utangnya.
116
Rudhy A. Lontoh, et.al., Op.Cit., hlm. 122 117
Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan
Harta Pailit (edisi revisi), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
63
3) Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih.
Mengenai syarat “jatuh waktu dan dapat ditagih” berdasarkan
penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan
adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu
baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya
sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh
instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter
atau majelis arbiter.118
Dengan demikian, syarat ini mengenai
utang yang sudah waktunya untuk dibayar, berdasarkan undang-
undang maupun perjanjian. Ketentuan ini menyatukan syarat utang
yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih.
Penyatuan tersebut ternyata dari kata “dan” di antara kata “jatuh
waktu” dan “dapat ditagih”,119
walau sebenarnya kedua istilah
tersebut berbeda pengertian dan kejadiannya.
Dengan demikian, kepailitan merupakan suatu proses, di mana
seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk
membayar utangnya, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal
ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat
membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para
kreditur, sesuai dengan peraturan pemerintah.120
e. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang
Kepailitan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang
berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga
adalah sebagai berikut:
1) Debitur sendiri.
2) Seorang atau lebih kreditur.
118
Imran Nating, ibid hlm. 26 119
Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hlm. 57. 120
Rudhy A. Lontoh, et.al., Op.Cit., hlm. 23.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
64
3) Kejaksaan, kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan
pailit untuk kepentingan umum dengan syarat bahwa ketentuan
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan terpenuhi dan
tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit
atas debitur itu.
4) Bank Indonesia, apabila debitur merupakan bank maka
permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank
Indonesia
5) Bapepam, permohonan pernyataan pailit yang debiturnya
merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya
dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
Menteri Keuangan.
6) Menteri Keuangan, apabila debitur merupakan Perusahaan
Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan
Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang
Kepailitan.
f. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit.
Tata cara pengajuan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan
niaga diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang
Kepailitan sebagai berikut.
Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh seorang debitur,
kreditur atau pihak lain ke pengadilan niaga dengan memenuhi
syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.
Permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga
kemudian Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan
pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan
diajukan. Setelah permohonan pernyataan pailit itu didaftarkan maka
Panitera Pengadilan Niaga akan menyampaikan permohonan
pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga. Setelah itu,
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
65
pengadilan akan mempelajari permohonan pernyataan pailit tersebut
dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan
pernyataan pailit diselenggarakan paling lambat 20 (dua puluh) hari
setelah tanggal permohonan didaftarkan namun sebelumnya juru sita
pengadilan niaga wajib melakukan pemanggilan para pihak terlebih
dahulu yaitu :
1) Debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh
kreditur, Kejaksaan, Bapepam, Bank Indonesia atau Menteri
Keuangan;
2) Kreditur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh
debitur dan terdapat keraguan jika syarat untuk dinyatakan pailit telah
terpenuhi.
Apabila dalam sidang pemeriksaan terdapat fakta atau keadaan
yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan
pailit telah terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit tersebut harus
dikabulkan. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana tersebut
adalah fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh
waktu dan tidak dibayar. Selama putusan pernyataan pailit belum
diucapkan, setiap kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau
Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan
untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan
debitur dan menunjuk Kurator sementara (Balai Harta Peninggalan atau
orang yang ditunjuk pengadilan untuk mengurus dan membereskan
harta pailit) untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur, pembayaran
kepada kreditur dan pengalihan kekayaan debitur. Putusan pernyataan
pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah
tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Hal ini merupakan
perwujudan dari asas peradilan cepat, murah dan sederhana.
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan
yaitu putusan atas permohonan pernyataan pailit yang memuat secara
lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
66
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan
terlebih dahulu meskipun terhadap putusan atas permohonan pernyataan
pailit tersebut diajukan suatu upaya hukum.
Dari rumusan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa putusan atas
permohonan pernyataan pailit mempunyai sifat “dapat dilaksanakan
terlebih dahulu” yang sering disebut dengan putusan serta-merta
(uitvoerbaar bij voorraad). Putusan serta-merta yaitu suatu putusan
yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi terlebih dahulu meskipun
putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Ekonomi Syariah.
a. Hubungan antara Ekonomi dan Hukum Islam.
Kegiatan ekonomi, bisnis, termasuk di dalamnya kegiatan
keuangan syariah, dalam sistem ajaran Islam masuk dalam kategori
muamalah, yang merupakan bagian dari ibadah dalam arti luas. Relasi
kegiatan ekonomi dengan hukum Islam dapat dilihat dalam tabel
berikut ini:121
Hukum Ekonomi Relasi
Ibadah mahdlah Zakat, infaq, dan sadaqah Pemerataan pendapatan
Munakahat Nafkah, dan harta bersama Memenuhi kebutuhan pokok
Mawaris Wasiat dan tirkah Takhaluf
Muamalah
maliyyah
Jual beli, sewa menyewa, dan
lain -lain
Akad/perikatan
Pidana Larangan mencuri, menipu, riba
dan lain-lain
Hifzh al-mal/memelihara
harta
Politik Sumber pendapatan negara;
ghanimah, fa’i, jizyah, dan ZIS
Pemerataan pendapatan dan
pengembangan masyarakat
Tabel 1.1. Relasi Kegiatan Ekonomi dengan Hukum Islam
121 Fathurrahman Djamil,Op. Cit. hlm. 22
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
67
Kegiatan ekonomi sebagai bagian dari muamalah menjadi objek
bahasan dalam hukum muamalah. Dalam fikih muamalah maliyah,
pembahasan utamanya meliputi: pertama, tentang hukum benda, yang
membahas tentang konsep harta, hak dan kepemilikan, dan kedua
tentang transaksi atau hukum akad, yang membahas masalah akad,
jenis - jenis akad dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya.
Bagi seorang muslim tujuan utama dalam berbisnis adalah
keberkahan, dimana ciri utamanya adalah kemaslahatan. Agar bisnis
yang mendapatkan keberkahan, Feddy Fabachrain berpendapat bahwa
setidaknyakita harus memenuhi tiga syarat.122
1) Pertama, bisnis yang dijalankan atas dasar ridha tanpa adanya
paksaan. Allah SWT berfirman,“Wahai orag-orang yang
beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan
perdagangan yang berlaku atas dasar suka diantara suka diantara
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Alllah
Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa’: 29)
2) Kedua, produk yang ditransaksikan bisnis harus barang yang
bermanfaat, bukan produk haram dan hak milik penuh penjual atau
mendapatkan izin pemilik bila bukan miliknya.
3) Ketiga, pihak penjual tidak boleh menyembunyikan cacat dari
suatu produk atau berlaku curang dari segi kualitas ataupun
kuantitas. Dari ‘Uqbah bin ‘Amir, ia berkata : Saya mendengar
Rasulullah SAW bersabda, “Orang Islam adalah saudara orang
Islam yang lain. Tidak halal bagi orang Islam menjual suatu
barang yang ada cacatnya pada saudaranya kecuali dengan
menerangkan cacatnya”.123
122
Direktorat Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah Komite Nasional Keuangan Syariah
(KNKS), Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS),
Jakarta, 2019, hlm. 47-48 123
Muhammad Nashiruddin Al-Abani, Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2, Pustaka, Azam, Jakarta,
2013, hlm. 755
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
68
Dunia saat ini sedang memasuki era budaya global dengan
kemajuan teknologi informatika di satu sisi dan kebangkitan
nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Budaya global juga ditandai
dengan era “ekonomi baru”, dan posisi hukum semakin diperlukan
guna mengaturnya.124 Budaya global juga antara lain disemarakkan
dengan perkembangan konsep “ekonomi Islam”. llmu ekonomi Islam
adalah ilmu tentang manusia yang menyakini nilai-nilai hidup Islam.
Ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial
melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia. Ilmu Ekonomi
Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam. Dalam aktivitas
ekonomi, individu harus memperhitungkan perintah Al Quran dan
Sunah, ekonomi Islam125 yang merupakan hasil serangkaian
“reaktualisasi” doktrin Islam tentang masalah ekonomi yang memasuki
fase aplikasi dalam beragam bidang ekonomi seperti keuangan lainnya.
126
Doktrin ekonomi Islam muncul pada abad XX, dimaksudkan untuk
membangun sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan wahyu
(Islamic scepture) dan tradisi yang melingkupinya. Diawali pada tahun
1940-an dan baru tiga dekade kemudian konsep hukum ekonomi islam
mulai muncul di berbagai negara.127
Saat ini pemerintah Pakistan,
Malaysia dan beberapa negara lain mulai menerapkan program
sentralisasi sistem redistribusi Islam, yaitu zakat. Lebih dari 60 negara
memulai Bank Islam dengan menawarkan sistem free interest yang
124
Abd. Shomad, Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah, Yuridika, Vol 16, No. 4, Juri-
Agustus, 2001, hlm. 343. 125
Periksa lebih lanjut dalam M. Abdul Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, terjemahan M.
Nastangin, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Dana Bhakti Waqaf, Yogyakarta, 1997, hlm. 19-
21. 126 Abd. Shomad, Op.Cit, hlm. 72. 127
Eksistensi kajian hukum ekonomi Islam modern diulas dalam Yusuf Qardhawi, Norma dan
Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1987, hlm. 19-21 ;
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
69
disebut sebagai alternatif dari bank dengan sistem bunga.128
Perkembangan doktrin ini bermula dari benua India dan didukung
momen penting dalam kasus boming minyak di tahun 1970-an. Pada
tahun 1975 didirikan Islamic Development Bank dengan maksud untuk
memberikan bantuan bagi perkembangan negara berkembang muslim
dengan pinjaman tanpa bunga. Kemudian dimulailah perbaikan-
perbaikan infrastruktur ekonomi Islam, sekolah-sekolah bisnis Islam
didirikan di sejumlah negara Islam, begitu pula dengan penerbitan
jurnal-jurnal ekonomi Islam dan pertemuan reguler lembaga donor.
Sejak itu ekonomi Islam ditampilkan sebagai disiplin akademis. Riset
digalakkan tatkala muncul masalah dari berbagai model aplikasi dari
ekonomi Islam termasuk sistem redistribusi dan Bank Islam menjadi
diskursus baru.129
b. Prinsip Ekonomi Syari’ah
Zainul Arifin dalam tulisannya, Prinsip-prinsip Operasional Bank
Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar, antara lain:
1) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang
sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia
harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam
produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia,
yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Namun yang terpenting
adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung jawabkannya di
akhirat nanti.
2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu,
termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama,
kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan
128
Perkembangan Perbankan Islam diulas dalam Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis,
Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek dan Prospek, terjemahan Burhan Wirasubrata, Perbankan
Syariah, Prinsip, Praktek dan Prospek Serambi, Jakarta, 2003, hlm.14-29. 129
Lebih lanjut baca dalam Timur Kuran, Politik Indentitas Ekonomi Islam, Gerbang, Vol. S No.
02, Oktober-Desember, 1999.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
70
kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak
sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima
upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada
tuntutan Allah SWT dalam Al-Qur'an.
4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital
produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan
yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan
dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri
didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri
yang merupakan kepentingan umum. Islam menjamin kepemilikan
masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan
orang banyak.
5) Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, oleh
karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan
yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk
diskriminasi dan penindasan.
6) Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (nisab)
diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi
sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan
harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan orangorang
yang membutuhkan.
7) Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai
bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman,
perusahaan perorangan, pemerintah maupun institusi lain.130
130
Zainul Arifin, Prinsip-prinsip Operasional Bank Islam, Tazkia.com, 22 November 2000., lihat
juga : Zainul Arifln, Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya, Jurnal Hukum
Bisnis, Vol. 11, 2000, hlm. 146.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
71
Dalam sistem ekonomi Islam aktivitas keuangan dan perbankan
dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk
membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Qur'an, yaitu untuk
saling membantu dan bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk
kebaikan serta mengolah uang yang ada agar dapat berputar dalam
transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat misalnya dalam hal
perniagaan. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, manusia dan
faktor kemanusiaan merupakan unsur utama. Faktor kemanusiaan
dalam ekonomi Islam terdapat dalam kumpulan etika yang terdapat di
dalam Alqur’an dan hadis serta tertulis di dalam buku-buku klasik
(turath) yang mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap
moderat, dan persaudaraan.131
Sjaichul Hadi Permono dalam salah satu bukunya “Formula Zakat,
Menuju Kesejahteraan Sosial”, mengidentifikasi beberapa prinsip
ekonomi Islam, yakni:132
1) Prinsip Keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan
prinsip yang penting, sebagaimana Allah memerintahkan untuk
berbuat adil di antara sesama manusia dalam banyak ayat antara
lain:
a) QS. an-Nahl: 90, ”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu)
berlaku adil dan bebuat kebajikan, memberi bantuan kepada
kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji,
kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.133
b) QS. Al-Maidah:8, “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah
kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi
saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu
131
Maskur Rosyid, Dimensi Kemanusiaan dalam Sistem Ekonomi Islam ( Sebuah Kajian dengan
Pendekatan Filsafat Hukum Islam, Khazanah (Jurnal Studi Islam dan Humaniora) , Vol. 13,
No.1, Juni 2015, hlm. 61 132 Sjaichul Hadi Permono, Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial, Aulia, Surabaya, 2005,
hlm. 46-49. 133
Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit., hlm. 551.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
72
kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah.
Karena (adil) itu dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada
Allah, sungguh, Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”.134
c) QS. al-Hasyr:7, “Harta rampasan fai' yang diberikan Allah
kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri,
adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim,
orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam
perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang –
orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul
kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu
maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh,
Allah sangat keras hukuman-Nya ”.135
2) Prinsip Al Ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada
orang lain lebih daripada hak orang lain itu.
3) Prinsip al mas'uliyah (accountability, pertanggungjawaban), yang
meliputi beragam aspek, yakni: pertanggung jawaban antara
individu dengan individu (Mas 'uliyah fil-afrad), pertanggung
jawaban dalam masyarakat (mas'uliyah al-mujtama'). Manusia
dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi
terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan,
serta tanggung jawab pemerintah (mas'uliyah al-daulah),
tangungjawab ini berkaitan dengan baitulmal.
4) Prinsip al kifayah (sufficiency), tujuan pokok dari prinsip ini
menurut Sjaichul Hadi Permono adalah untuk membasmi kefakiran
dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam
masyarakat.
5) Prinsip Keseimbangan, prinsip al-wasathiyah ( al-I’tidal, moderat,
keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-
batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan
134
Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit., hlm. 213. 135
Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit., hlm. 1089
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
73
individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini tampak dari beberapa
firman Allah antara lain:
a) QS. al-Isra’:29, “Dan janganlah engkau jadikan tanganmu
terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu
mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela
dan menyesal.” ;136
b) QS. al-Furqan: 67, “Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan yang
Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan
(harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di
antara keduanya secara wajar.”137
c) QS. al-Isra’:27,”Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu
adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada
Tuhannya”. 138
d) QS. al-An’am:141, “Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-
tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma,
tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang
serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya).
Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya
(zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berlebih-lebihan”. 139
6) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi
akhlak karimah.
a) Prinsip transaksi yang meragukan dilarang. akad transaksi harus
tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad.
maupun harga barang yang diakadkan itu.
b) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang
merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga
136
Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit., hlm. 567 137
Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit., hlm. 727 138
Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit., hlm. 565. 139
Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit., hlm. 289
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
74
dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah: “Tidak boleh
membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh
membahayakan (merugikan) pihak lain.”
c) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini
menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus
didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.
d) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat,
transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat
dilarang.
e) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
f) Prinsip suka sama suka (saling rela, an taradhin). Prinsip ini
berlandaskan pada firman Allah dalam Al-Qur’an Surat an-Nisa
ayat 29 : “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak
benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar
suka diantara suka diantara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang
kepadamu.”140
Prinsip ini juga berlandaskan hadits nabi: “tidak
lain jual beli harus melalui jalan suka sama suka” (HR. Ibnu
Majah). 141
g) Prinsip tiada paksaaan. Setiap orang memiliki kehendak yang
bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksanaan
transaksi apa pun, kebuali hal yang diharuskan oleh norma
keadilan dan kemaslahatan masyarakat.
140
Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit., hlm. 163. 141
Muhammad Nashiruddin Al-Abani, Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2, Pustaka, Azam, Jakarta,
2013, hlm. 755
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
75
c. Dasar Hukum Kontrak Ekonomi Syariah (Akad Syariah)
Landasan syariah tentang kontrak142
selain terkait langsung dengan
kewajiban menunaikan akad dalam QS. Al-Maidah ayat 1143
dan QS.
Al-Isra ayat 34144
, juga memuat tentang adanya kewajiban membuat
catatan tertulis ketika menjalankan transaksi bisnis yang dilakukan
tidak secara tunai. Suatu transaksi yang dilakukan secara tunai
(naqdan) tidak ada keharusan untuk menuliskannya. Tetapi apabila
akad yang dibuat tidak secara tunai (ghairu naqdan) maka wajib untuk
menuliskannya, kerena penulisan perjanjian selain berfungsi sebagai
alat bukti, juga bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaannya.
Allah berfirman dalam QS. Al Baqarah 282 :
“ Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang
piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya
sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia
menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan
hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia
mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika orang yang berutang itu
orang yang kurang akalnya atau lemah (keadannya), atau tidak mampu
mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan
benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara
kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang
laki-laki dan dua perempuan diantara orang – orang yang kamu sukai,
dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang
142 James Gordley menyebutkan bahwa belum ada teori tentang kontrak yang diakui secara
umum. Hal tersebut disampaikan dalam The Philosophical Origins of Modern Contract
Doctrine sebagai berikut.
“ Today, we have no generally recognized theory of contract. The objective theories have
lost even the limited support among jurists they once enjoyed. It is not helpful to define
contract as a series of consequences the law attaches to the outward conduct of the parties if
one cannot explain why the law attaches some consequences rather than others. There is
widespread agreement that any viable theory of contract will have to take the fairness of a
contract into account, yet there is no agreement as to how to do so.” Lihat : James Gordley, The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine, Clarendon
Press, Oxford, 1991, hlm. 230. 143
Q.S. al-Maidah ayat 1 : “Hai orang-orang yang beriman ! Penuhilah janji-janji.”
Janji di sini adalah janji setia hamba kepada Allahh dan perjanjian yang dibuat oleh manusia
dalam pergaulan sesamanya”.
Lihat Terjemahan :Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit., hlm. 207-208. 144
QS. al-Isra’ ayat 34 : “... dan penuhilah janji. Karena janji itu akan akan dimintai
pertanggungjawabannya”
Lihat Terjemahan :Kementrian Agama Republik Indonesia, ibid. hlm. 567
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
76
seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak
apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk
batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian
itu, lebih adil disisi Allah lebih dapat menguatkan kesaksian,
mendekatkan kamu kepada ketidakraguann, kecuali jika hal itu
merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu,
maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan
ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis
dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian),
maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah
kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu”.145
d. Tujuan Kontrak Syariah
Dalam pandangan Islam, suatu perbuatan harus senantiasa
diniatkan kepada Allah semata (lillahita’ala). Niat yang baik Allah
kemudian harus diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang sesuai
dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkanNya. Ketentuan ini
mengacu pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh
Bukhari yang menegaskan bahwa sesungguhnya amalan itu tergantung
dari pada niatnya. Dan setiap amal perbuatan seseorang akan dinilai
sesuai dengan apa yang diniatkan. Berdasarkan hadits tersebut, berlaku
kaidah fiqh yang menyatakan bahwa segala perkara (perbuatan) akan
dinilai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuannya.
e. Asas-Asas Kontrak Syariah
Rumusan asas-asas dalam hukum kontrak syariah bersumber dari
Al-Qur’an dan Sunnah. Upaya ini dimaksudkan agar asas-asas yang
dijadikan sebagai dasar hukum penyusunan kontrak mengandung
kebenaran yang bersumber dari Allah. Apabila digali ari sumber syariat,
kebenaran asas-asas yang terkait dengan hukum kontrak jumlahnya
sangatlah beragam, antara lain:146
1) Asas Ibadah (Asas Diniatkan Ibadah)
145
Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit., hlm. 93 146 Burhanuddin, Hukum Kontrak Syari’ah, BPFE, Yogyakarta, 2009, hlm. 41
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
77
Hakekat kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada
Allah147
. Dengan demikian adanya keyakinan terhadap unsur
ketuhanan dalam aspek Ibadah, merupakan hal yang prinsip dalam
Islam. Bentuk keyakinan ini harus diwujudkan melalui amalan niat
(aqidah) sebelum memulai perbuatan. Disamping aqidah, suatu
perbuatan akan bernilai ibadah apabila sesuai dengan hukum syara’
yang telah ditetapkan. Keberadaan asas inilah yang menjadi
perbedaan mendasar antara hukum kontrak syariah dengan hukum
kontrak lainnya.
2) Asas Harriyyah at-Ta’aqud (Asas Kebebasan Berkontrak)
Asas Harriyyah at-Ta’aqud merupakan wujud dari asas
kebebasan berkontrak. Masing-masing pihak yang akan mencapai
tujuan akad mempunyai kebebasan untuk mengadakan penyusunan
kontrak (freedom of making contract). Ruang lingkup kebebasan
berkontrak dapat berupa kebebasan: (1) menentukan objek perjanjian,
(2) mengajukan syarat-syarat dalam memutuskan hak dan kewajiban,
dan (3) menentukan cara penyelesaian apabila terjadi
perselisihan/sengketa.
Pengertian asas kebebasan berkontrak dalam Islam berbeda
dengan apa yang dimaksud kebebasan berkontrak dalam hukum
konvensional. Perbedaannya bahwa kebebasan berkontrak dalam
Islam ialah kebebasan yang bersifat terikat dengan hukum syara’.
Karena bersifat terikat maka kebebasan berkontrak itu akan
dibenarkan selama syarat-syarat yang dikemukakan tidak
bertentangan dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum
kebebasan berkontrak yang bersifat mengikat antara lain :
a) “Kaum muslimin itu setia kepada syariat-syariat yang mereka
buat, kecuali syariat mengharamkan yang halal dan
menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi, Tabrani dan Baihaqi).
147 QS. Adz-Dzariyat ayat 56 : “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka menyembah-Ku”
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
78
b) “Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang mereka
sepakati, selama masih berada dalam lingkup kebenaran” (HR.
Bukhari)
c) “Bagaimana nasib kaum yang menyepakati syarat-syarat (dalam
bermuamalah) yang tidak sesuai dengan Al-Qur’an? Barangsiapa
yang menyepakati sebuah syarat yang tidak sesuai dengan Al-
Qur’an, maka syarat tersebut tidak sah meskipun mereka
menyepakati hingga seratus kali” (Hadits Shahih).
3) Asas Al-Musawah (Asas Persamaan)
Muamalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan
sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam
memenuhi kebutuhan hidup, Allah telah melebihkan sebagian karna
dari sebagian yang lain dalam hal rezeki148
. Namun hikmah yang
dapat diambil dari adanya perbedaan tersebut ialah agar diantara
mereka saling membutuhkan kerja sama149
. Dengan adanya perilaku
saling membutuhkan, maka setiap manusia memiliki kesamaan hak
untuk mengadakan perikatan. Dikatakan demikian, karena pada
prinsipnya manusia adalah sama. Sedangkan yang membedakan
hanya ketakwaannya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat
ayat 13, “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami
jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling
mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
148
QS. An-Nahl ayat 71, “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam
hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki
mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu.
Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?.” 149
QS. Az-Zukhruf ayat 32, “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah
meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian
mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa
yang mereka kumpulkan.”
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
79
ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Mahateliti.150
4) Asas At-Tawazun (Asas Keseimbangan)
Meskipun secara faktual masing-masing pihak yang akan
mengadakan kontrak memiliki berbagai latar belakang yang berbeda,
namun dalam hukum Islam tetap menekankan perlunya berpegang
pada asas keseimbangan. Karena asas keseimbangan dalam akad
terkait dengan pembagian hak dan kewajiban. Misalnya adanya hak
mendapatkan keuntungan dalam investasi, berarti harus disertai
dengan kewajiban menanggung resiko. Ketentuan ini merujuk pada
kaidah fiqh yang menyatakan keuntungan muncul bersama resiko dan
hasil usaha muncul bersama tanggungan yang dikeluarkan.
5) Asas Maslahah (Asas Kemaslahatan)
Pada hakekatnya, tujuan mengadakan akad ialah untuk
mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Pengertian
maslahat dalam Islam meliputi dimensi kehidupan dunia dan akhirat.
Dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan maka kaidah fiqh
yang berlaku yaitu apabila hukum syara’ dilaksanakan maka pastilah
tercipta kemaslahatan.
Namun apabila dalam pelaksanaan akad ternyata terjadi suatu
perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kemudharatan
pihak lain, maka kaidah fiqh yang berlaku adalah segala apa yang
menyebutkan terjadinya kemudharatan (bahaya) maka hukumnya
haram 151
Untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah timbulnya
kemudharatan dalam fiqh dijumpai adanya hak khiyar. Maksud hak
khiyar ialah hak yang memberikan opsi para pihak untuk meneruskan
atau membatalkan akad karena adanya sebab yang dapat merusak
keridhaan. Hak khiyar berlaku pada akad yang bersifat belum pasti.
150
Kementerian Agama Republik Indonesia, Op. Cit, hlm. 1031 151
Burhanuddin, Hukum Kontrak Syari’ah, BPFE, Yogyakarta, 2009, hlm. 44
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
80
Sedangkan apabila pelanggaran terjadi setelah perikatan yang bersifat
pasti (luzum), maka yang berlaku bukan lagi hak khiyar, melainkan
pemberian hak berupa tuntutan mendapatkan ganti rugi kepada para
pihak yang merasa dirugikan.
6) Asas Al-Amanah (Asas Kepercayaan)
Asas amanah merupakan bentuk kepercayaan yang timbul
karena adanya iktikad baik dari masing-masing pihak untuk
mengadakan akad. Dalam hukum kontrak syariah, terdapat bentuk
akad yang bersifat amanah. Maksud amanah disini dapat diartikan
sebagai kepercayaan kepada pihak lain untuk menjalin kerja sama.
Asas kepercayaan dapat berlaku baik dalam akad yang bersifat
tijarah maupun tabbaru’. Dalam akad tijarah misalnya kepercayaan
shahibul maal kepada mudharib untuk menjalankan usaha melalui
akad mudharabah.
Sedangkan akad yang bersifat taharru’ misalnya memberikan
kepercayaan kepada orang lain untuk memelihara barang titipan
melalui akad wadiah. Dasar hukumnya ialah firman Allah:
a) QS. An-Nisa ayat 58, ”Sungguh, Allah menyuruhmu
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya , dan
apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya
kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik
yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha
Mendengar, Maha Melihat. ”;152
b) QS. Al-Baqarah ayat 283, “Dan jika kamu dalam perjalanan
sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah
ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu
memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa
kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan
kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh
152
Kementerian Agama Republik Indonesia, Op. Cit, hlm. 171
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
81
hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.”; 153
c) QS. Al-Anfal ayat 27, “Wahai orang – orang yang beriman!
Janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul dan (juga)
janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan
kepadamu, sedang kamu mengetahui.”154
7) Asas Al-‘Adalah (Asas Keadilan)
Para pihak yang melakukan akad penyusunan kontrak, wajib
berpegang teguh pada asas keadilan, Pengertian asas keadilan ialah
suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan
pada prinsip kebenaran hukum syara’. Karena itu dengan berbuat
adil, maka seseorang tidak akan berlaku zalim terhadap yang lain,
Untuk itu Allah berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 8 sebagai
berikut:
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak
keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan
janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih
dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh,
Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”.155
8) Asas Al-Ridha (Asas Keridhaan)
Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan
diantara masing-masing pihak. Apabila dalam transaksi tidak
terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta dengan
cara batil. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29 :
“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),
kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka
153
Kementerian Agama Republik Indonesia, Op. Cit, hlm. 95 154
Kementerian Agama Republik Indonesia, Op. Cit, hlm. 157 155
Kementerian Agama Republik Indonesia, Op. Cit, hlm. 213
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
82
diantara suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”156
Berdasarkan ayat tersebut jelas, bahwa segala kontrak perjanjian
hendaklah berdasarkan pada asas keridhaan. Dengan demikian tanpa
adanya unsur keridhaan, maka suatu kontrak perjanjian masuk dalam
kategori batil.
9) Asas Al-Kitabah (Asas Tertulis)
Kontrak merupakan perjanjian/perikatan yang dibuat secara
tertulis. Namun perlu dipahami bahwa dalam Islam asas tertulis (al-
kitabah) tidak hanya berlaku dalam hukum kontrak, melainkan juga
berlaku pada semua akad muamalah yang dilakukan tidak secara
tunai ( utang) Allah WST berfirman dalam QS. Al Baqarah ayat 282:
“Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang
piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya dengan benar.”
10) Asas As-Shiddiq (Asas Kejujuran)
Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam
segala bidang kehidupan, termasuk dalam penyusunan kontrak
muamalah. Jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan
kontrak, maka akan merusak keridhaan (‘uyub al-ridha). Disamping
itu, ketidakjujuran dalam penyusunan kontrak akan berakibat
perselisihan diantara para pihak. Allah berfirman dalam QS. Al-
Ahzab ayat 70 : “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kamu kepada Allah, dan ucapkanlah perkataan yang benar”.157
Demikian pula Rasulullah SAW bersabda :
a) “Apabila engkau melakukan jual beli, maka katakanlah,” Tidak
ada tipu-menipu”158
;
156
Kementerian Agama Republik Indonesia, Op. Cit, hlm. 163 157
Kementerian Agama Republik Indonesia, Op. Cit, hlm. 851 158
Arif Rahman Hakim (Penerjemah), Kumpulan Hadits Shahih Bukhari-Muslim (cetakan ke-12),
Insan Kamil, Surakarta, 2014, hlm. 443. Buku asli ditulis oleh Muhammad Fu’ad Abdul Baqi
dengan judul Al-Lu’lu’ wal Marjan.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
83
b) “Barangsiapa yang melakukan penipuan, maka dia tidak
termasuk golongan kami” (HR. Ibnu Majah)159
11) Asas Iktikad Baik
Untuk mengadakan kontrak perjanjian harus dilaksanakn
berdasarkan iktikad baik. Asas iktikad baik muncul dari pribadi
seseorang sebagaimana apa yang telah diniatkannya. Dalam
pandangan Islam, niat merupakan prinsip mendasar terkait dengan
unsur kepercayaan(aqidah) sebelum melakukan suatu amal
perbuatan. Dalil syariah yang menjadi dasar hukum berlakunya asas
itikad adalah hadits Rasulullah yang menyatakan bahwa
sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat dan
sesungguhnya tiap-tiap orang tergantung dari apa yang diniatkannya
(HR. Bukhari)
f. Rukun-Rukun Akad
Rukun dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang menentukan
terbentuknya akad. Tanpa keberadaan rukun, suatu akad tidak akan
terjadi. Namun agar akad menjadi sah, maka unsur-unsur pembentuk
akad harus memenuhi syarat sebagai rukun. Carron-Ann Russell
menyebutkan ada 3 unsur yang harus ada dalam suatu kontrak agar
kontrak dapat ditegakkan secara hukum yaitu 1) kesepakatan antara
para pihak (penawaran dan penerimaan), 2) tawar-menawar
(pertimbangan); dan 3) niat kontrak.160
Menurut kalangan fuqaha, terdapat keragaman pendapat berkenaan
dengan rukun akad. Namun menurut pendapat jumhur fuqaha, rukun-
rukun akad terbagi menjadi:161
1) Aqidain (Para Pihak)
159
Muhammad Nashiruddin Al-Abani, Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2, Pustaka, Azam, Jakarta,
2013, hlm. 755 160 Carron-Ann Russell, Opinion Writing and Drafting in Contract Law, Cavendish Publishing
Limited, London, 1996, hlm. 8. Lihat juga : Max Young, Understanding Contract Law,
Routledge, London, 2010, hlm. 8. 161 Burhanuddin, Op.Cit., hlm. 23
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
84
Aqidain (para pihak yang berakad) dipandang sebagai rukun
kontrak karena merupakan salah satu pilar utama tegaknya akad.
Tanpa aqidain sebagai subjek hukum, suatu kontrak tidak mungkin
dapat terwujud. Pengertian subjek hukum berarti perbuatan
manusia yang dituntut oleh Allah berdasarkan ketentuan hukum
syara’. Subjek hukum merupakan pelaku perbuatan menurut syara’
dapat menjalankan hak dan kewajiban.
Subjek hukum terdiri dari dua macam, yaitu manusia dan badan
hukum. dalam rukun akad, kedua subjek hukum tersebut
berkedudukan sebagai aqidain. Namun agar aqidain dapat
mengadakan kontrak perjanjian secara sah, maka harus memenuhi
syarat kecakapan (ahliyah) dan kewenangan (wilayah) bertindak di
hadapan hukum..
a) Manusia.
Manusia (syakhshiah thabi’iyah) dikatakan sebagai subjek
hukum karena memang fitrah perbuatan manusia terikat oleh
hukum syara’162
, keterikatan perbuatan manusia pada hukum
syara’ dimaksudkan untuk selalu beribadah mengharap
keridhaan Allah163
. Karena keabsahan ibadah seseorang selain
162 QS. Al-Jatsiyah ayat 18, “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengiuti syariat (
peraturan) dari agama itu, maka ikutilah ( syariat iu) dan janganlah engkau ikuti keinginan
orang-orang yang tidak mengetahui.”
Lihat : Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit. 997 163
QS. Al-Baqarah ayat 207, “Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya
untuk mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.”
Lihat : Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit. 91
QS. Al-Baqarah ayat 265, “Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk
mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak
di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua
kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun (pun memadai). Allah Maha
Melihat apa yang kamu kerja.”
Lihat : Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit. 87
QS. An-Nisa ayat 114, “Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka
kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat
kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian
karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberi nya pahala yang besar.”
Lihat : Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit. 191
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
85
ditentukan oleh unsur kebenaran niat (aqidah), juga ditentukan
oleh kesesuaian antara perbuatan dengan hukum syara’.
Perbuatan seseorang dikatakan memiliki kecakapan sebagai
subjek hukum apabila memenuhi dua kriteria persyaratan,
yaitu:
Pertama, memiliki kecakapan (ahliyah). Dalam hukum Islam,
seseorang dapat menjadi subjek hukum ialah karena memenuhi
syarat kecakapan. Menurut fiqh, syarat kecakapan terbagi
menjadi dua :
(1) Ahliyah al-wujub, merupakan kecakapan seseorang untuk
menerima hukum. maksud dari menerima hukum disini
ialah menerima hak dan memikul kewajiban. Dalam
menerima hukum, suatu kecakapan bersifat pasif sehingga
dapat berlaku bagi semua manusia secara keseluruhan,
mulai dari kondisi dalam kandungan hingga manusia
meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan fiqh, syarat
kecakapan menerima hukum (ahliyat al-wujub) dapat
dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
(a) Kecakapan menerima hukum tidak sempurna (ahliyah
al-wujub an-naqishah) ialah kecakapan menerima
hukum yang berlaku bagi subjek hukum yang masih
dalam kandungan.
(b) Kecakapan menerima hukum secara sempurna (ahliyah
al-wujub al-kamilah). Kecakapan ini berlaku bagi
subjek hukum setelah dilahirkan hingga meninggal
dunia. Dikatakan sempurna karena subjek hukum selain
mampu menerima hak juga dapat memikul
kewajiban164
.
(2) Ahliyah al-ada, merupakan kecakapan untuk bertindak
hukum secara aktif. Karena bersifat aktif, kecakapan ini
164
Syamsul Anwar, Op.Cit. hlm. 111
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
86
berlaku hanya bagi subjek hukum yang secara alamiah telah
memiliki kemampuan bertindak hukum. Untuk dapat
bertindak hukum, subjek akad harus memenuhi syarat
kecakapan al-ada. Dalam fiqh kecakapan al-ada dapat
dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
(a) Kecakapan bertindak hukum secara tidak sempurna
(ahliyah al-ada an-naqishah) ialah kecakapan yang
berlaku bagi subjek hukum ketika berada pada usia
tamyiz. Usia tamyis merupakan syarat kecakapan
minimal bagi para pihak yang akan mengadakan akad.
Namun dalam akad tertentu, usia tamyiz dianggap tidak
memenuhi syarat kecakapan sebelum mencapai usia
kedewasaan.
(b) Kecakapan bertindak hukum sempurna (ahliyah al-ada
al-kamilah) ialah kecakapan yang berlaku bagi subjek
hukum sejak memasuki dewasa hingga meninggal
dunia.
Syarat kecakapan al-ada dimiliki oleh subjek hukum
sejak memasuki usia tamyiz dan berlangsung terus
hingga meninggal dunia. Namun kecakapan bertindak
hukum pada usia tamyiz ini tidaklah sempurna sebelum
seseorang memiliki kematangan akal (aqil) dan
mencapai usia kedewasaan (baligh). Menurut pendapat
jumhur fuqaha, kedewasaan itu pada pokoknya
diketahui dari tanda-tanda fisik berupa ihtilam atau
haid. Namun bilamana tanda-tanda itu tidak muncul,
maka kedewasaan ditandai dengan usia yang telah
mencapai 15 tahun.
b) Badan Hukum Syariah.
Istilah badan hukum (syakhshiah i’tibariyahhukmiyah)
tidak disebutkan secara khusus dalam pandangan fiqh. Namun
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
87
keberadaan badan hukum dibenarkan dalam fiqh, meskipun
istilah itu belum ada pada masa lalu165
. Badan hukum dikatakan
sebagai subjek hukum karena terdiri dari kumpuln oramg-orang
yang melakukan perbuatan hukum (tasharruf). Badan hukum
merupakan hasil analogi dari keberadaan manusia sebagai
subjek hukum. Ketentuan menjadikan badan hukum sebagai
subjek hukum, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip
akad yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Keberadaan
badan hukum terkait dengan adanya penerapan akad wakalah
dalam pembagian tugas ( job discription) dari suatu manajemen
perusahaan. Dalam hal ini manusia bertindak sebagai wakil
dari organ lembaga atau perusahaan tersebut. Meskipun atas
nama badan hukum seseorang menjalankan amanah
perusahaan, namun sebagai pertanggungjawaban vertikal tetap
dikembalikan kepada amalan individu masing-masing.166
Dalam sejarah peradaban Islam, lembaga-lembaga yang
pernah disebut sebagai badan hukum ialah baitul mal, badan
waqaf, dan institusi negara167
. Sedangkan dalam konteks
kehidupan sekarang, keberadaan badan hukum dapat
diwujudkan dalam bentuk kelembagaan tertentu seperti:
peradilan agama, badan arbitrase syariah, perusahaan atau
lembaga ekonomi keuangan yang beroperasi berdasarkan
prinsip syari’ah. Karena badan hukum tersebut beroperasi
berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka dapat disebut badan
hukum syariah.
165
Ash Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi, Pengantar Fiqih Muamalah (Cet. Ke-4), Pustaka
Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 205 166
QS. Al-Muddatsir ayat 38,“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”
Lihat : Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit. 1149 167
Djazuli, Pengantar Edisi Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, Kiblat
Umat Press, Bandung, 2002, hlm. xxxi
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
88
Manusia yang bertindak atas nama diri sendiri maupun
badan hukum merupakan para pihak (aqidain) dalam
penyusunan kontrak. Karena itu agar para pihak dapat
melakukan penyusunan kontrak secara sah, maka para pihak
harus memenuhi syarat sebagai aqidain yang merupakan rukun
akad
2) Mahal al-‘Aqd (Obyek Akad)
Sebelum ijab qabul, rukun kedua yang harus dipenuhi dalam
penyusunan kontrak syariah adalah menentukan jenis objek akad
(mahal al-‘aqd). Pengertian objek akad ialah sesuatu yang oleh
syara dijadikan objek dan dikenakan padanya akibat hukum yang
ditimbulkan168
. Dengan kata lain, istilah objek akad dapat pula
diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan
manusia ketika akan melakukan akad.
Dari pengertian tersebut, pada dasarnya objek akad dapat
terbagi menjadi dua, yaitu (a) harta benda; dan (b) manfaat
perbuatan itu sendiri. Karena melalui kedua objek akad tersebut,
seseorang akan dapat mencapai tujuan akad sesuai dengan yang
dikehendakinya. Apabila objek berupa benda, maka syaratnya
harus halal dari segi zatnya (mal mutaqawim). Sedangkan apabila
objeknya berupa manfaat perbuatan, maka caranya harus
disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (masyru).
Dalam penyusunan kontrak syariah, keberadaan objek akad
yang dimiliki para pihak sangat menentukan jenis akad yang akan
digunakan. Misalnya orang yang ingin mendapatkan sesuatu, maka
harapannya akan tercapai segera setelah memenuhi rukun dan
syarat akad yang digunakan. Misalnya: apabila objeknya berupa
kepemilikan benda, maka akad yang digunakan jual beli.
Kemudian apabila objeknya berupa manfaat, berarti akad yang
168
Gufron A. Masadi, Fiqih Muamalah Kontekstual, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 86.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
89
digunakan ijarah. Dan suatu manfaat dapat dihasilkan baik melalui
objek benda maupun perbuatan.
Sedangkan bagi yang tidak mampu, kebutuhan terhadap objek
tertentu yang bersifat dharurat dapat diperoleh melalui akad
tabarru. Apabila objek kebutuhannya berupa manfaat/kepemilikan
benda, maka dapat dicapai dengan cara: (a) meminjamkan sesuatu
atau (b) memberikan sesuatu. Sedangkan apabila objeknya berupa
manfaat perbuatan, maka hanya dapat dilakukan dengan cara
memberikan pertolongan untuk melakukan sesuatu.
Menurut para fuqaha, agar sesuatu dapat dijadikan sebagai
objek akad yang merupakan bagian rukun akad maka harus
memenuhi persyarakatn sebagai berikut:
a) Sesuatu yang menjadi objek akad harus sesuai dengan prinsip
syariah (masyru’).
Karenanya apabila objek akad sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah, keberadaan objek akad akan memberi kemashlahatan
bagi manusia. Begitu pula sebaliknya apabila objek akad
bertentangan dengan prinsip syariah, pasti akan menimbulkan
kemudharatan. Dan segala sesuatu yang menimbulkan
kemudharatan menurut kaidah fiqh hukumnya diharamkan, baik
ditinjau dari keharaman zatnya (haram li dzatihi) maupun selain
zatnya (haram li ghairihi)
(1) Keharaman yang terkandung di dalam zatnya (haram li
dzatihi) misalnya: bangkai, darah, daging babi.169
Begitupula
169
QS. An-Nahl ayat 115, “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah,
daging babi dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barang
siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui
batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.”
Lihat : Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit. hlm. 557
QS.Al maidah ayat 90, “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras,
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji
dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu mendapat
keberuntungan.”
Lihat : Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit. hlm. 243
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
90
dalam hadits riwayat Jabir bin Abdullah disebutkan bahwa
sesungguhnya Allah SWT mengharamkan jual beli khamar,
bangkai, babi, dan patung-patung.170
(2) Keharaman selain zatnya (haram li ghairihi) misalnya riba,
gharar, tadlis, ihtikar, ba’i najasy, perjudian (maisir), riswah,
perzinaan, pencurian dan lain-lain yang terkait dengan cara
pelaksanaannya.
b) Adanya kejelasan objek akad sehingga dapat diserah terimakan.
Dasar hukum kejelasan objek akad mengacu pada sabda
Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad r.a,
“janganlah kaliyan membeli ikan yang masih dalam air, karena
merupakan penipuan (gharar)”.
Selain gharar, ketidakjelasan objek akad akan menjadi
penghalang terjadinya serah terima kepemilikan. Dalam suatu
riwayat, Hakim bin Hizam berkata: “Wahai Rasullulah,
sesungguhnya aku membeli barang dagangan, apa yang
dihalalkan dan diharamkan darinya?” Jika engkau membeli
sesuatu, maka janganlah engkau jual lagi sebelum barang
tersebut berada di tanganmu.” (HR. Ahmad Baihaqi dan Ibnu
Hibban). Demikian pula, Rasulullah bersabda dalam hadits yang
diriwayatkan oleh Muslim r.a. “Barangsiapa yang membeli
makanan, maka dia tidak boleh menjualnya sebelum dia
menerima barang tersebut.”171
Berdasarkan hadits tersebut dapat diambil kesimpulan
bahwa mengaitkan sesuatu yang belum diketahui, maka
hukumnya batal. Tetapi ada pengecualian terhadap akad-akad
tertentu seperti salam dan istishna, dengan syarat sebelum
pembuatan barang harus dijelaskan klarifikasinya. Dalam akad,
keberadaan objek merupakan sesuatu yang menjadi tujuan
170
Muhammad Fu’ad Abdul Baqi (Arif Rahman Hakim (penerjemah)),Op.Cit., hlm. 457. 171
Muhammad Fu’ad Abdul Baqi (Arif Rahman Hakim (penerjemah)), Op.Cit., hlm. 441
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
91
diadakannya akad. Keberadaan objek akad disyaratkan harus
jelas sehingga dapat diserah terimakan. Ditinjau dari segi
kejelasan objek yang dapat diserah terimakan, objek akad dapat
dibedakan menjadi dua macam yaitu:
(1) Bentuk objek akad berupa harta benda. Apabila objek
tersebut berupa harta bergerak (mal al-manqul), maka akad
dilakukan dengan cara penyerahan harta tersebut. Sedangkan
apabila bentuk objek akad berupa harta benda yang tidak
bergerak (mal al-‘uqar/mal ghairu munqul), maka
penyerahan cukup dilakukan dengan cara pengalihan hak
(sertifikat) kepemilikan bendanya.
(2) Apabila objek akad berupa manfaat, maka penyerahannya
dilakukan dengan cara menggunakan benda tersebut.
Sedangkan apabila objek akad berupa perbuatan, maka
penyerahannya dilakukan dengan cara menjalankan amanah
pekerjaan tersebut sesuai dengan manfaat yang diharapkan
pihak lain.
c) Adanya syarat kepemilikan sempurna terhadap objek akad.
Ketentuan ini mengacu pada hadits yang diriwayatkan oleh
Hakim bin Hizam r.a ketika mengadu kepada Rasulullah SAW,
hadist sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi ra, “Wahai
Rasululah, ada seorang yang datang kepadaku kemudian dia
menanyakan apakah saya ingin menjual barang, di mana barang
tersebut bukan milik saya”. Kemudian setelah mendengar
pengaduan tersebut Rasulullah SAW bersabda:“ Janganlah
menjual suatu barang yang bukan milikmu”
Dari keterangan hadits tersebut jelas bahwa pada dasarnya
Islam melarang transaksi terhadap objek akad yang bukan
menjadi kewenangannya. Mengadakan sesuatu tanpa
sepengatahuan pemiliknya dinamakan dengan akad fudhuli.
Dengan akad fudhuli menyebabkan keabsahan hukum akad
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
92
(mahal al-‘aqd) yang akan ditransaksikan, kemudian rukun
selanjutnya adalah sighat akad. Sighat akad merupakan hasil ijab
dan qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang menimbulkan
akibat hukum terhadap objeknya. Pernyataan ijab dan qabul
bertujuan untuk menunjukkan terjadinya kesepakatan akad. Ijab
ialah pernyataan pertama yang disampaikan oleh salah satu pihak
yang mencerminkan kehendak untuk mengadakan perikatan.
Sedangkan qabul adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab
yang mencerminkan persetujuan/kesepakatan terhadap akad.
Dengan demikian, ijab-qabul merupakan pernyataan kehendak
(al-iradah) yang menunjukkan adanya suatu keridhaan antara
dua orang atau lebih sesuai dengan ketentuan syara’.
3) Kesesuaian antara ijab dan qabul (Tathabuqbaina al-ijabwa al-
abul).
Tanpa adanya kesesuaian antara ijab dan qabul maka dengan
sendirinya akad tidak mungkin terjadi. Misalnya dalam transaksi
penyusunan kontrak jual beli (al-ba’i) ada seseorang pengusaha
yang menyatakan ingin membeli suatu barang sebagai penawaran
harganya dianggap belum sesuai. Ketidaksesuaian antara ijab dan
qabul inilah yang mengakibatkan penyusunan kontrak jual beli
tidak jadi terlaksana.
4) Para pihak hadir dalam suatu majelis akad (majlis al-‘aqd).
Sebagian fuqaha menembahkan persyaratan bahwa akad harus
dilakukan dalam satu majelis.172
Tetapi perlu waktu, mengingat
perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan seseorang
untuk melakukan transaksi bisnis jarak jauh, misalnya e-commerce.
Namun dalam hukum kontrak, adanya sudah cukup beralasan.
Karena pada bagian penutup penyusunan kontrak, selalu memuat
tempat yang harus ditandatangani para pihak.
172
Gufron A. Masadi, Op.Cit, hlm. 94
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
93
5. Kepailitan dalam Perspektif Islam (Taflis)
a. Pengertian Taflis.
Terkait kompetensi Pengadilan Agama yang memiliki
kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
ekonomi syariah, dalam hal kepailitan, sesungguhnya dalam agama
Islam juga mengenal kepailitan dengan istilah taflis. Taflis satu akar
dengan fulūs yang berarti uang.173
Dalam arti bahasa adalah tidak
mempunya harta atau pekerjaan yang bisa menutupi
kebutuhannnya.174
Dalam bahasa fiqh digunakan kata iflās yang
berarti tidak mempunyai harta atau fulūs.175
Seseorang yang
dinyatakan pailit disebut muflis. Biasanya muflis dianggap sebagai
orang yang tidak memiliki harta, orang yang kapitalnya habis dan
kefakirannya ini mencapai pada keadaan dimana dimana ia dikatakan
sebagai orang yang tidak mempunyai uang. Hal tersebut sebagaimana
Hadits nabi :
Artinya: Dari Abi Hurairah bahwa Rasulallah SAW. Berkata:
tahukah kamu apa muflis itu? Mereka menjawab: Muflis menurut
kami adalah mereka yang tidak mempunyai dirham (uang) dan
kapitalnya habis (HR. Muslim).176
Iflas, sebagaimana Penulis sampaikan sebelumnya yang juga
merupakan padanan kata pailit, mengandung pengertian bahwa iflas
ialah jumlah nominal utang seseorang lebih besar dari harta yang
dimilikinya, meskipun orang tersebut semula tergolong mampu atau
mempunyai harta tetapi jumlahnya lebih kecil dari utangnya. Dalam
173
Hasan Muarif Ambary, Suplemen Ensiklopedi Islam, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 90 174 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madhab, Lentera, Jakarta, 1999, hlm. 700 175 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 191-192 176
Abi Khusain Muslim, Shahih Muslim (Juz IV), Dar Al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, Tanpa
Tahun, hlm. 45.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
94
hukum al-Iflas, jika utang yang dimiliki oleh debitur lebih besar dari
harta yang dimilikinya, sementara pihak kreditor meminta agar orang
tersebut dilarang untuk membelanjakan hartanya (hajr), maka hakim
wajib menyatakan pailit terhadap debitor itu.177
Ruang lingkup taflis sebagai suatu kebangkrutan dalam
penelitian ini adalah dalam bidang mualamah atau ekonomi. Hal ini
perlu ditegaskan mengingat terdapat Hadist Rasulullah yang
diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi dan Ahmad tentang
bangkrut.
Bahwa Rasulullah Saw pernah berdiskusi dengan para
sahabatnya tentang definisi orang yang merugi. "Tahukah kalian
siapa orang yang bangkrut?" tanya Rasulullah. Para sahabat
berpendapat, orang bangkrut adalah mereka yang tidak
mempunyai dirham maupun dinar. Ada juga yang berpendapat
mereka yang rugi dalam perdagangan. Rasulullah SAW
bersabda:
"Orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang datang
pada Hari Kiamat dengan banyak pahala shalat, puasa, zakat,
dan haji. Tapi di sisi lain, ia juga mencaci orang, menyakiti
orang, memakan harta orang (secara bathil), menumpahkan
darah, dan memukul orang lain. Ia kemudian diadili dengan
cara membagi-bagikan pahalanya kepada orang yang pernah
dizaliminya. Ketika telah habis pahalanya, sementara masih ada
yang menuntutnya maka dosa orang yang menuntutnya
diberikan kepadanya. Akhirnya, ia pun dilemparkan ke dalam
neraka." (HR. Muslim, no. 2581)178
177
Ali bin Muhammad, Mu’jam al-Isthilahaat al-Iqtishadiyyah wa al-Islamiyyah, Maktabat al-
“Abiikan, 2000, hlm. 63. Dalam Siti Anisah, Op.Cit, hlm 398 178
Imam An Nawawi, Syarah Shahih Muslim , Darus Sunnah, Jakarta, 2012, no. 2581
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
95
Para ulama fiqh sepakat mendefinisikan taflis dengan rumusan
keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak secara hukum
atas hartanya karena terlilit hutang yang meliputi atau bahkan
melebihi hartanya. Apabila seseorang pedagang (debitur)
meminjamkan modal dari orang lain (kreditur) dan ternyata usaha
perdagang tidak lancar, sehingga seluruh dagangannya habis maka
atas permintaan kreditur kepada hakim, debitur dapat dinyatakan
pailit sehingga segala tindakan hukumnya terhadap sisa harta
miliknya dapat dicegah. Pencegahan tindakan hukum debitur pailit
ini bertujuan untuk menjamin hutangnya pada kreditur.179
Para ulama sepakat bahwa seorang muflis tidak dilarang
menggunakan hartanya sebesar apapun hutangnya kecuali sesudah
adanya larangan dari hakim. Kalau dia menggunakan seluruh
hartanya sebelum adanya larang dari hakim, maka tindakannya itu
dinyatakan berlaku. Para piutang dan siapa saja tidak berhak
melarangnya sepanjang hal itu tidak dimaksudkan untuk melarikan
diri dari hutang atau menggelapkan hak-hak orang lain yang ada
pada dirinya, khususnya bila tidak ada harapan untuk bertambahnya
penghasilan berdasarkan kenyataan yang ada.180
Hakim tidak boleh melarang muflis untuk membelanjakan
hartanya kecuali dengan syarat-syarat berikut ini:181
(a) Orang tersebut betul-betul berhutang dan hutangnya telah
terbukti secara syar’i;
(b) Disepakati bahwa hartanya tidak melebihi jumlah hutangnya;
(c) Hutangnya tersebut sudah saatnya dibayar, bukan yang masih
mempunyai tenggang;
(d) Hendaknya pelarangan itu berdasarkan permintaan seluruh atau
sebagian dari orang-orang yang mempunyai hutang.
179
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Intermasa, Jakarta, 1997, hlm. 1361 180
Mughniyah, FiqhLima Madhab, PT. Lentera Basritama, Jakarta, 1996, Jakarta, hlm.700. 181
Ibid.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
96
b. Dasar Hukum Taflis
Menurut ulama fiqh, seseorang debitur atas pengaduan kreditur
dapat diajukan sebagai Tergugat ke pengadilan sehingga ia dikatakan
pailit. Pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh as-
Daruqurutni dan al-Hakim yang berbunyi182
:
Dalam hadits tersebut diatas diriwayatkan bahwa nabi Muhammad
SAW menyatakan Mu’adh sebagai orang yang terlilit hutang dan tidak
mampu melunasinya. Kemudian Rasulullah melunasi hutang tersebut
dengan sisa harta yang dimiliki Mu’adh. Karena para pemberi hutang
merasa piutangnya tidak sepenuhnya terlunasi, maka mereka melakukan
protes terhadap Rasulullah. Protes tersebut kemudian dijawab oleh
Rasulullah dengan mengatakan tidak ada yang bisa diberikan kepada
kamu selain itu.
Berdasarkan hadits diatas, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa
seorang hakim berhak menetapkan pernyataan pailit seorang debitur
karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Oleh sebab itu, hakim
yang menyatakan seorang debitur jatuh pailit berhak melarang debitur
pailit bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya dan hakim berhak
pula melunasi hutang debitur pailit dari sisa hartanya sesuai dengan
prosentase hutangnya.
182
Sayyid Shabiq, Op.Cit., hlm. 456.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
97
Ulama fiqh juga menyatakan bahwa dalam soal hutang-piutang,
sebagai hakim tidak boleh melakukan intervensi terhadap orang lain,
karena kaidah umum dalam shari’at Islam menyatakan bahwa hak orang
lain dipelihara oleh shara’.183
Akan tetapi, dalam kasus debitur tidak
mampu lagi membayar hutangnya karena hartanya tidak ada lagi atau
hartanya tidak cukup untuk membayar seluruh hutang, maka ulama fiqh
sepakat membolehkan hakim melakukan intervensi untuk menyelesaikan
hutang. Salah satu pertimbangannya menurut para ahli Fiqh adalah
banyaknya pihak kreditur yang mengajukan tunututan kepada hakim.
Dalam riwayat lain, yang juga menjadi salah satu dasar hukum taflis
adalah hadits nabi Muhammad SAW tersebut berbunyi:
“Dari Ibnu Kaab bin Malik dari Ayahnya r.a. bahwa sesungguhnya
Rasulullah SAW. Menahan barang kepunyaan Mu’adh dan beliau
menjualnya untuk melunasi hutangnya yang menjadi bebannya”.184
Artinya: ...Amma ba’du, wahai sekalian manusia sesungguhnya Usafi’
adalah Usafi’ dari Juhainah. Ia telah merelakan agama dan kejujurannya
untuk dikatakan bahwa ia mendahulukan semua kebutuhan dan bahwa ia
telah berhutang tanpa melunasinya sehingga menjadi dua periuk atasnya.
Maka barang siapa mempunyai hutang atasnya, hendaknya mereka datang
kepada kami.185
183
Nasrun Haroen, Op.Cit. 192 184
Ali Ibnu Umar at-Daruqutni, Sunan at-Daruqutni (J.II), Dar al-Fikr, Beriut, tanpa tahun, hlm.
125. 185
Malik bin Anas, Muwatto( J.II), Al-Kutub, Beirut. Tanpa Tahun, hlm. 70.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
98
Selain hadits sebagaimana tersebut diatas, beberapa hadits
meriwayatkan tentang taflis :186
1) Diriwayatkan dari Abu Huraihah, ia berkata : “Aku mendengar
Rasulullah SAW, bersabda : “Barang siapa yang mendapati hartanya
yang benar-benar miliknya pada seorang yang telah pailit, maka ia
lebih berhak untuk mengambilnya daripada orang lain” (Hadits
disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim)187
2) Diriwayatkan Amr putera Syarid, ra., dari ayahnya, ia berkata
:”Bersabda Rasulullah SAW.: “ Orang yang mengundur-ngundur
pembayaran hutang, padahal ia mampu membayarnya, maka halal
diambil barangnya atau didera” (Hadits diriwayatkan oleh Imam Abu
Dawud dan Imam Nasa’i).
3) Dari Abu Sa’id Al Khudri, ra., ia berkata: “ Seorang lelaki pada
zaman Rasulullah SAW. merasa rugi dalam berjualan buah-buahan
yang ia jual, sehingga mengakibatkan banyak hutangnya. Maka
bersabda Rasulullah SAW.: “Berilah dia sedekah (zakat), lalu orang-
orangpun memberinya, tetapi tidak cukup untuk membayar
hutangnya sampai lunas.” Kemudian Rasulullah SAW bersabda
kepada orang-orang yang mengutangkannya: “Ambillah apa-apa
yang ada pada dia, tetapi tidak ada sedikitpun padanya selain itu”
(Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim).188
Berdasarkan pada Q.S. An-Nisa ayat 5189
dan ayat 6190
, Mohsen
Alhamad berpendapat tentang pembekuan aset sebagai berikut :191
186 Moh. Machfuddin Aladip, Terjemahan Bulughul Maram, Karya Besar Al-Hafizh Ibn Hajar
Al-Asqalani, Karya Toha Putra, Semarang, Tanpa Tahun, hlm. 427-430. 187
Muhammad Fu’ad Abdul Baqi (Arif Rahman Hakim (penerjemah)),Op.Cit., hlm. 457. 188 Imam An Nawawi, Syarah Shahih Muslim (Jilid 7), Darus Sunnah, Jakarta, 2012, 189 “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akal sehatnya, harta
(mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.
Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka
perkataan yang baik.”
Terjemahan firman Allah pada QS. An-Nisa ayat 5 tersebut diatas, dan seterusnya Penulis
menggunakan terjemahan dari Kementrian Agama Republik Indonesia, Syaamil Al-Qur’an
Miracle The Preference, Sygma Publishing, Bandung, 2010, hlm. 151.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
99
The freezing of assets is two kinds:
1) The freezing for the benefit of others ( as freezing someone's
money who is bankrupt for his debtors).
2) The freezing for his own protection so he does not waste it, that is
in the cases of the minor, absent minded, and the mentally ill.
Kemudian Mohsen Alhamad berpendapat bahwa:
There are two forms of debtors:
1) The first case is if the debt is due and he is not to pay until the debt
is due, and if his net worth is less than his debt his assets will not
be frozen ,nor he will be prohibited from using his money.
2) If the debt is due now, there are two cases:
a) when his net worth is more than the debt: in this case no
withholding of his money,but he is told to pay his debtors, and
if he refuses he is punished and jailed. If he endured the
punishment and prison and refuses to pay, then the ruler is to
pay his debts from telling his assets enough to cover the debt.
b) if his net worth is less than his debt, then his assets are frozen
and it is published that his assets are withheld so people do not
deal with him.
If after selling his assets and it was not enough to cover the debt,
he still owes this money until he is able to pay , this remaining debt
does not vanish due to his bankruptcy.
c. Pernyataan Pailit (Taflis) dalam Islam.
Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh tentang pernyataan
pailitnya seseorang dan statusnya di bawah pengampuan, apakah
perlu ditetapkan melalui keputusan hakim atau tidak. Ulama madhab
Maliki dalam persoalan ini memberikan pendapat secara terperinci,
sebagai berikut:
190
“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika
menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada
mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas
kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa.
Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari
memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu
menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka,
maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi.”
Lihat: Ibid., hal. 151 191
Mohsen Almahad, Bankruptcy in Islamic Law
(Syaria)https://www.linkedin.com/pulse/20141113092630-314687442-bankruptcy-in-islamic-
law-sharia, diakses 25 Juni 2018.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
100
(1) Sebelum seseorang dinyatakan pailit, para kreditur berhak
melarang debitur bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya
dan hak mereka, seperti mewariskan dan menghadiakan
hartanya, dan melakukan akad mudharabah dengan orang lain.
Tindakan hukum yang bersifat jual beli dapat dibenarkan.
(2) Persoalan hutang piutang ini tidak diajukan kepada hakim, pihak
debitur dan pihak kreditur dapat melakukan as-sulh
(perdamaian). Dalam kaitannya dengan ini, debitur pailit tidak
diperbolehkan bertindak secara hukum yang sifatnya
memindahkan hak milik atas sisa hartanya, seperti wasiat, hibah,
dan kawin. Apabila tercapai perdamaian, maka para kreditur
berhak membagi sisa harta pihak debitur pailit sesuai dengan
prosentase piutangnya.
(3) Pihak kreditur mengajukan gugatan (seluruh atau sebagian)
kepada hakim agar pihak debiturdinyatakan pailit, serta
mengambil sisa hartanya untuk membayar hutang-hutangnya.
Gugatan yang diajukan harus disertai dengan bukti bahwa hutang
pihak debitur melebihi sisa hartanya dan waktu pembayaran
hutang telah jatuh tempo.apabila hakim telah menetapkan
pernyataan pailit kepada pihak debitur, maka pihak kreditur
berhak mengambil sisa harta pihak debitur dan membagi-baginya
sesuai dengan prosentase piutang masing-masing.
Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa seseorang
dinyatakan pailit hanya berdasarkan ketetapan hakim, sehingga
apabilah belum ada keputusan hakim tentang statusnya sebagai
debitur pailit, maka segala bentuk tindakan hukumnya dinyatakan
masih tetap sah. Sebaliknya, apabila debitur telah dinyatakan oleh
hakim, maka hakim berhak melarangnya untuk tidak bertindak
secara hukum terhadap sisa hartanya, apabila perbuatannya akan
membawa mudharat kepada hak-hak pihak kreditur, dan hakim juga
berhak menjadikannya di bawah pengampuan serta menahannya.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
101
Dalam masa tahanan, hakim boleh menjual sisa harta debitur pailit
dan membagi-bagikannya kepada kreditur, sesuai dengan prosentase
piutang masing-masing.192
d. Akibat Hukum Taflis ( Kepailitan) bagi Debitor Pailit.
1) Dibawah Pengampuan
Ulama fiqh mengemukakan beberapa akibat hukum tentang
dinyatakan seseorang jatuh pailit dan statusnya di bawah
pengampuan. Akibat hukumnya antara lain:
a) Sisa harta debitur pailit menjadi hak para kreditur. Oleh karena
itu, debitur pailit tidak dibenarkan bertindak secara hukum atas
sisa hartanya. Hal ini kesepakatan para ulama fiqh.
b) Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa debitur yang telah
dinyatakan pailit oleh hakim, boleh dikenakan tahanan sementara
sampai hutangnya dibayar. Akan tetapi, mereka berbeda
pendapat dalam pengawasan terus-menerus terhadap debitur
pailit. Ulama Madhab Hanafi berpendapat bahwa para kreditur
boleh mengawasi tindak tanduk pailit secara terus-menerus193
Menurut Madhab Maliki, Madhab Shafi’i dan Madhab
Hambali, apabila hakim berpendapat bahwa debitur pailit berada
dalam kesulitan, maka para kreditur tidak menuntutnya dan
mengawasinya terus-menerus. Menurut mereka, debitur pailit
seperti ini harus dibebaskan untuk mencari rezeki sampai ia
berkelapangan untuk membayar hutangnya.194
e. Penyitaan Harta Muflis (Debitor Pailit)
Para ulama Madhab Maliki berpendapat bahwa penetapan pailit
pada seseorng hanya dapat diterima jika diterapkan melalui putusan
hakim. Jika keputusan hakim belum ada, orang tersebut bebas
192
Abdun Nashir, Nadhariyah al-Ajal Fi al-Litizam Fi ash-shari’ah al-Islamiyah Wa al-
Qawaanun al-Arabiyah, TP, Mathba’ as-Sa’adah, 1978, hlm. 260. 193
Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj. M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, ash-Shifa’,
Semarang, 1990, 333-334. 194
Ibid.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
102
melakukan tindakan hukum terhadap hartanya. Madhab Maliki
mengemukakan pendapat tentang seseorang yang jatuh pailit sebagai
berikut:195
a) Sebelum seseorang dinyatakan pailit, para pemberi hutang
berhak melarangnya untuk bertindak hukum terhadap harta yang
masih dimiliki serta membatalkan segala tindakan hukum yang
membawa mudharat kepada hak-hak mereka, seperti melakukan
hibah, wakaf, dan sedekah terhadap hartanya, namun jika bersifat
jual beli, boleh dilakukan.
b) Jika persoalan tidak sampai diajukan kepada hakim, maka orang
yang pailit bisa melakukan perdamaian dengan pemberi hutang.
Para pemberi hutang dibolehkan mengambil hartanya serta
membagi-bagikan kepada pemberi hutang lainnya sesuai dengan
prosentase piutangnya Dalam hal ini al-Shaukani membolehkan
menyita harta orang yang pailit untuk membayar hutangnya,
sekalipun harta tersebut tidak memadai untuk membayar
hutangnya secara keseluruhan.196
Menurut al-Shaukani yang
boleh disita hanya selain pakaian yang dipakainya, rumah tempat
tinggalnya, dan hajat hidup yang primer. Jika segenap hartanya
disita, hal demikian termasuk sebagai tindakan penganiayaan
atas dirinya.
c) Adanya ketetapan hakim bahwa seseorang itu dinyatakan pailit.
Untuk mendapatkan ketetapan hakim bahwa seseorang itu
dinyatakan pailit perlu adanya gugatan dari pemberi hutang
(sebagai atau seluruhnya) kepada hakim dengan syarat hutangnya
melebihi harta yang dimiliki orang tersebut dan sudah jatuh
tempo pembayaran. Jika ketetapan hakim telah ada, maka
pemberi hutang berhak atas harta orang yang pailit tersebut
sesuai dengan prosentase piutang masing-masing.
195
Ibid. 196
Nasrun Rusli,Konsep Ijtihad al-Shaukani, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, hlm. 191.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
103
2) Penyanderaan
Kelompok yang berpendapat bahwa debitur dalam hal ini
disandera (bukan disita kekayaannya) menurut Ibnu Rushd,
berpedoman pada hadith Nabi SAW sebagai berikut:
Artinya: Mangkirnya orang yang mampu menghalalkan
kehormatan dan penghukumannya.197
Dalam syarah kitab Sunan an-Nasai oleh Jalaluddin as-Suyuti
yang dimaksudkan hukum penghukuman, menurut para ulama
adalah penyanderaan.198
Tetapi dua sahabat Imam Abu Hanifah
yang utama, yaitu Ya’qub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari dan
Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani
Artinya: “Jika kreditur si bangkrut (yaitu debitur) meminta
pelarangan membelanjakan kekayaan maka hakim mengabulkan
dan melarang berniaga, membelanjakan dan menyatakan (adanya
kreditur lain selain para kreditur yang memohonkan pelarangan)
sehingga tidak merugikan para kreditur. Dan hakim menjual
kekayaan si pailit jika si pailit menolak menjualnya sendiri dan
membaginya (hasil penjualan) untuk para kreditur sesuai
perbandingan piutang masing-masing.’’199
f. Berakhirnya Kepailitan (Taflis)
Mengenai hal ini, ulama Madhab Syafi’I dan Hambali
mengemukakan dua pendapat:
197
Ibn Rusyd, Op.Cit., 333 198
Mughniyah, Op.Cit., 700 199
Muhammad Abu Zahrah, Muhaadlorot fi Taarikh al-Madzaahib al-Fiqhiyah, Dar-alKutub al-
Ilmiyah, Beirut, 1996, 185.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
104
1) Apabila harta muflis telah dibagi-bagikan kepada para pemberi
hutang sesuai dengan prosentasenya (sekalipun tidak lunas), maka
status di bawah pengampuan dinyatakan hapus, karena sebab yang
menjadikan ia berada di bawah pengampuan telah hilang. Mereka
menganalogikan antara orang yang berada di pengampuan
disebabkan gila. Bagi orang gila yang telah sembuh dari
penyakitnya, maka statusnya sebagai orang yang berada di bawah
pengampuan gugur dengan sendirinya, tanpa harus ditetapkan oleh
putusan hakim. Demikian juga dengan muflis. Hal ini sejalan
dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan: hukum itu beredar
sesuai dengan penyebabnya, apabila ada penyebabnya maka ada
hukumnya, dan apabila penyebabnya sudah hilang, keadaannya
kembali seperti semula.
2) Pembatalan status orang yang berada di bawah pengampuan harus
dilakukan dengan keputusan hakim, karena penetapan ia berada di
bawah pengampuan juga berdasarkan keputusan hakim. Dalam hal
ini, Wahbah az-Zuhaili (guru besar Fiqh dan Ushul fiqh)
menyatakan bahwa ketetapan hakim dalam menentukan status
seseorang berada di bahwa pengampuan harus mempunyai syarat.
Apabilah syarat tersebut syarat tersebut terpenuhi oleh orang yang
dinyatakan pailit, maka secara otomatis statusnya bebas dari
pengampuan tanpa harus melalui ketetapan hakim terlebih dahulu.
Namun kebebasan statusnya ini perlu disebarluaskan agar
masyarakat mengetehauinya, sehingga tidak merugikan dirinya
dalam melakukan transaksi ekonomi.
Mazhab Hanafi berpendapat apabila ternyata tidak ada lagi harta
untuk membayar hutang kepada kreditur, maka debitur dibebaskan
sejalan dengan surat al- Baqarah ayat 280
Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280 :
(e)
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
105
“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu
menyedekahkan itu, lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahui.”200
Madhab Syafi'I, Malik, Abu Yusuf dan Muhammad,
membolehkan penjualan harta debitur atas permintaan
krediturnya. Diriwayatkan oleh Abu Hanifah, bahwa tidak boleh
dilakukan pengawasan terhadap orang yang berhutang, dan tidak
boleh menjual kekayaannya. Al-Syaukani membolehkan menyita
harta orang yang bangkrut (pailit) untuk membayar hutangnya,
sekalipun harta tersebut tidak memadai untuk membayar
hutangnya secara keseluruhan.
6. Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan dengan Pendekatan Maqashid
Al- Syari’ah.
a. Pengertian Maqashid Al-Syari’ah.
Secara etimologi, maqashid al-syari’ah terdiri dari dua kata, yakni
maqashid dan syari’ah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshud
yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapu syari’ah artinya jalan
menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber
kehidupan.
Adapun secara terminologi, beberapa pengertian tentang maqashid
al-syari’ah yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara
lain :
200
Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit. hlm. 91
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
106
1) Al-Imam al-Ghazali, penjagaan terhadap maksud dan tujuan
syari’ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan
faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.201
2) Al-Imam al-Syatibi, Al-Maqashid terbagi menjadi dua: yang
pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat Syari’ah,
dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf.202
3) ‘Alal al-Fasi, maqashid al-syari’ah merupakan tujuan pokok
syari’ah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh
Tuhan.203
4) Ahmad al-Rasyuni, maqashid al-syari’ah merupakan tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan oleh syari’ah untuk dicapai demi
kemaslahatan manusia.204
5) Abdul Wahab Khallaf, tujuan umum ketika Allah menetapkan
hukum-hukumNya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan
manusia dengan terpenuhinya keutuhan yang dlaruriyah, hajiyah,
dan tahsiniyah.205
b. Pendekatan Maqashid Al- Syari’ah dalam Memutus dan Memeriksa
Perkara.
Pendekatan maqashid al Syari’ah dalam memeriksa dan
memutuskan perkara sangat perlu dilakukan oleh hakim karena dengan
menggunakan pendekatan maqashid al Syari’ah, akan terwujud hukum
yang berkeadilan dan berdasarkan kepada kebenaran, yang semuanya
201
Al-Ghazali, Shifa al-Ghalil, Tahqiq Hamdi Ubaid al-Kabisi, Mathna’ah al-Irshad, Baghdad,
1971, hlm. 159 dalam Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi
Islam: Perspektif Maqhasid al-syari’ah, Kencana PrenadaMedia, Jakarta, 2014, hlm. 41 202
Jamal al-Din “athiyyah, Al-Nadzariyah al-Ammah li al-Syari’ah al-Islamiyah, 1988, hlm. 102
dalam Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, ibid hlm. 42 203
Bin Zaghibah Izz al-Din, Al-Maqashid al-Ammah li al-Syari’ah al-Islamiyah, Dar al-Shafwah
li al-Thaba’ah wa al-Tauzi, Kairo, 1996, hlm. 44 dalam Dalam Ika Yunia Fauzia dan Abdul
Kadir Riyadi, ibid hlm. 42 204
Ahmad al-Raysuni, Nadzariyah al-Maqashid Inda al-Imam al-Syathibi, AlMa’had al-Ali al
Fikr al-Islami, al-Jami’iyah li al-Dirasat wa al-Nashr wa-alTawzi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 45
dalam Dalam Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, ibid hlm. 43 205
Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Dar al-Qalam li al-Nashr wa al-Tawzi, 1990, hlm.
171 dalam Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, ibid hlm. 43
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
107
bermuara kepada terwujudnya kemashlahatan bagi masyarakat.
Terwujudnya kemashlahatan yang ditandai dengan lahirnya putusan
yang adil dan benar merupakan tujuan Allah dalam menetapkan
hukum.
Teori tentang Maqashid al Syari’ah adalah teori yang perlu
dikuasai dan dipahami oleh hakim (terutama hakim pada Pengadilan
Agama) dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan. Artinya,
bagaimana seorang hakim bisa melakukan analisis filosofis terhadap
perkara yang sedang dihadapinya. Maka pertanyaan-pertanyaan yang
muncul ketika memeriksa perkara adalah pertanyaan yang betul-betul
menjurus kepada inti dari kasus yang sedang diperiksa. Begitu juga
dalam memutuskan perkara tersebut, yaitu bagaimana hakim
mengunakan landasan pemikiran hukum yang berdasarkan kepada
maqashid al Syari’ah. Sehingga putusan hukum yang diambil oleh
hakim bisa mendatangkan kemashlahatan dan menolak kemudharatan
bagi kedua belah pihak yang berpekara.206
Hal tersebut diatas pada prinsipnya telah diatur dalam Pasal 27 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan
Kehakiman :
“ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat”
Demikian pula dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam
dinyatakan bahwa:
“Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang
diajukan kepadanya, wajib mempertahankan dengan sungguh-
sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat,
sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat”
206
Doni Dermawan, Pendekatan Maqashid Al Syari'ah Dalam Memeriksa Dan Memutuskan
Perkara, http://www.pa-muarasabak.go.id/home/arsip-berita/arsip-berita/pendekatan-
maqashid-al-syariah-dalam-memeriksa-dan-memutuskan-perkara1, diakses tanggal 1
September 2018.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
108
Inti dari maqashid al Syari’ah adalah untuk mencapai
kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah
untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-
tujuan syara’. Adapun tujuan syara’ yang harus dipelihara itu adalah
1) menjaga agama, 2) menjaga jiwa, 3) menjaga akal, 4) menjaga
keturunan dan 5) menjaga harta.207
Berdasarkan hal tersebut, dapat
dikatakan bahwa seseorang mukallaf akan bisa memperoleh
kemashlahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima
prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan
jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut.208
Upaya yang harus ditempuh dalam rangka mewujudkan
kemashlahatan itu, menurut Muhammad Said Ramadhan al Buthi
ada lima kriteria yang harus dipenuhi, yaitu209
, pertama
mempriotaskan tujuan-tujuan Syara’, kedua tidak bertentangan
dengan al Qur’an, ketiga tidak bertentangan dengan al Sunnah,
keempat tidak bertentangan dengan prinsip qiyas karena qiyas
merupakan salah satu cara dalam menggali hukum yang intinya
adalah untuk memberikan kemashlahatan bagi mukallaf. Dan kelima,
memperhatikan kemashlahatan yang lebih besar.
Penerapan teori maqashid al Syari’ah dalam proses memeriksa
dan memutus perkara-perkara pada Pengadilan Agama, secara
praktik digunakan dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan
yang berkaitan dengan inti kasus yang sedang diperiksa. Artinya,
bagaimana seorang hakim bisa menemukan fakta-fakta yang
sebenarnya dari kasus tersebut, melalui pertanyaan-pertanyaan yang
berdasarkan kepada analisis filosofis terhadap kasus yang sedang
dihadapi. Untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan tersebut,
207
Al Gazhali, Abu Hamid, al Mustashfa Min Ilm al Ushul, Dar al Kutub al Ilmiyyah, Beirut,1983
hlm. 286-287 208 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah,Logos Wacana Ilmu,
Jakarta, 1995, hlm. 38 209
Muhammad Said Ramadhan al Buthi, al Dawabit al Mashlahat fri al Syari’ah al Islamiyah,
Muasasah al Risalah, Beirut, 1977, hlm. 140-141
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
109
maka yang harus dilakukan oleh hakim adalah merumuskan masalah
pada perkara yang sedang dihadapi. Perumusan pokok masalah
dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan oleh hakim
merupakan kunci dari proses penerapan hukum yang tepat dan benar.
Penerapan maqashid al Syari’ah dalam memutuskan perkara,
maka yang menjadi pertimbangan hakim adalah teori kemashlahatan
hukum, dalam artian, hakim sebagai penterjemah atau pemberi
makna melalui penemuan hukum (rechtschepping) dan menciptakan
hukum baru melalui putusan-putusannya (judge made law), harus
bisa mewujudkan kemashlahatan bagi masyarakat (terutama pihak
yang berpekara) dalam setiap putusannya. Sehingga tidak ada pihak-
pihak yang merasa menang dan yang merasa kalah, karena putusan
hakim sudah memberikan kemashlahatan dan menolak
kemudharatan bagi pihak-pihak yang berpekara.
Adapun pertimbangan kemashlahatan yang perlu diperhatikan
adalah asas kulliyah al Khamsah, yaitu 1) menjaga agama, 2)
menjaga jiwa, 3) menjaga akal, 4) menjaga keturunan dan 5)
menjaga harta. Khusus untuk Pengadilan Agama, maka
pertimbangan kemashlahatan yang perlu dijaga adalah 1) menjaga
agama, 2) menjaga keturunan, dan 3) menjaga harta, karena perkara
yang dihadapi Pengadilan Agama berkaitan dengan hukum keluarga
Islam yang lebih menekankan tiga aspek ini, yaitu agama, keturunan
dan harta sedangkan untuk Pengadilan Niaga Syari’ah yang hendak
digagas oleh Penulis, kemaslahatan yang perlu dijaga adalah
menjaga agama dan harta benda.
c. Perlindungan terhadap Agama.
Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama
adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama
berhak atas agamanya dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk
meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
110
ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.210
Dasar hak ini sesuai firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 :
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam),
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang
sesat”.211
Tujuan menjaga agama ini mempunyai kekuatan hukum syar’i,
yaitu dengan adanya wahyu berupa ayat-ayat Al-Qur’an maupun
Hadits, hal ini dikarenakan muatan sumber hukum utama tersebut
pada intinya menjaga agama dan aplikasinya pada segala aspek
kehidupan manusia, ketentuan Q.S. Al-Baqarah ayat 256 mengenai
tiada paksan dalam Islam merupakan norma hukum fundamental yang
harus ditaati, karena disinilah letak jati diri dan kewibawaan agama
Islam di mata umat manusia.212
Terhadap maqashid syari’ah memelihara agama dapat
dikategorikan menjadi tiga peringkat antara lain:213
1) Hifz al din daruriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan
kewajiban agama yang bersifat primer, seperti melaksanakan lima
rukun Islam.
2) Hifzh al din hajjiyat, yaitu melaksankan ketentuan agama dengan
menghindari kesulitan-kesulitan yang muncul dalam
pelaksanaannya atau dengan kata lain ada suatu kemudahan dalam
210
Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syari’ah, Amzah, Jakarta, 2009, hlm. 1 211
Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit. hlm. 81. 212
Prawitra Thalib, Syariah: Konsep dan Hermeneutika, Sharia Research and Training Unit (
SHAREAT) Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Lutfansah Mediatama, Surabaya,
2013, hlm. 71. 213
Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia (Cetakan Ketiga), Sinar
Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 18 dalam Prawitra Thalib, ibid.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
111
menjalankan kewajiban-kewajiban bersifat primer tersebut. Hal ini
dapat dicontohkan adanya kebolehan bagi seseorang untuk
menjama’ ataupun mengqhasarkan shalat lima waktu karena
adanya alasan-alasan tertentu, atau adanya kebolehan untuk
mengganti puasa dihari lain atau membayar sejumlah fidyah bagi
orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa dibulan ramadhan;
3) Hifzh al din tahsiniyyat, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban
agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, artinya dalam
melaksanakan perintah agama tidak hanya melengkapi kewajiban
kepada Allah SWT, melainkan juga sebagai pemenuhan kewajiban
terhadap sesama manusia, sebagai contoh muslim diharuskan
untuk menjaga kebersihan badan, pakaian dan tempat demi
mewujudkan kesempurnaan shalat, hal ini juga sebagaimana yang
disabdakan oleh Rasulullah SAW,”bahwa sesungguhnya
kebersihan itu adalah sebagian dari Iman”.
d. Perlindungan terhadap Harta Benda.
Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan,
dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi
untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah
kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai
penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini
dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara
yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini
harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.214
Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan bekerja dan
mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain
dengan cara batil. Allah juga mengharamkan riba. Apabila seseorang
meminjamkan hartanya kepada orang lain dalam bentuk utang, maka
dia bisa memilih salah satu diantara tiga kemungkinan berikut.
1) Meminta kembali hartanya tanpa imbalan,
214
Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Op.Cit, hlm. 167-169.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
112
2) Apabila tidak bisa mendapatkan maka dia harus bersabar dan tidak
membebaninya dengan melakukan tagihan,
3) Apabila orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, dia
dapat menyedekahkan pinjaman tersebut kepada peminjam yang
dalam keadaan miskin atau payah, karena nikmat harta harus
menjadi motivator untuk saling mengasihi, tidak untuk bersikap
antipati.
Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal.
Pertama, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari
tindak pidana pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta
orang lain ( baik dilakukan kaum muslimin atau non muslim) dengan
cara yang batil, seperti merampok, menipu atau memonopoli. Kedua,
harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur
mubazir atau menipu untuk hal-hal yang dihalalkan Allah.215
Selanjutnya, dilihat dari segi kepentingannya maka upaya
memelihara harta ini juga dapat dikategorikan menjadi tiga peringkat
yang antara lain adalah:216
a) Hifzh al mal daruriyyat, yaitu upaya pemeliharaan harta melalui
larangan untuk mendapatkan harta dengan cara yang tidak sah
atau melalui riba.
b) Hifzh mal hajjiyat, yaitu upaya pemeliharaan harta melalui
anjuran untuk mendapatkan harta melalui jalan yang halal
termasuk tata caranya, seperti contoh kebolehan unuk melakukan
kegiatan jual beli dan adab serta tata cara dalam melakukan jual
beli tersebut.
c) Hifz al mal tahsiniyyat, yaitu pemeliharaan harta melalui
kejujuran harta kekayaan dan menghindari musligat dalam
mendapatkan dalam harta kekayaan.
215
Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, ibid. hlm. 171. 216
Uswatun Hasanah, Human Rights In The Perspective of Islamic Law, Jurnal Hukum
International, Indonesian Journal of International Law, Volume 7 No. 4, Juli 2010, hlm. 727
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
113
7. Perbandingan Hukum.
a. Pengertian Perbandingan Hukum.
Perbandingan hukum adalah suatu pengetahuan dan metode
mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem
hukum, dengan meninjau kaidah dan/atau aturan hukum dan/atau
yurisprudensi seta pendapat ahli yang kompeten dalam berbagai
sistem hukum tersebut, untuk menemukan persamaan-persamaan dan
perbedaan-perbedaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan
dan konsep-konsep tertentu, dan kemudian dicari sebab-sebab
timbulnya persamaan dan perbedaan secara historis, sosiologis,
analitis, analitis, dan normatif.217
Selain itu, ada juga yang memberikan arti kepada perbandingan
hukum sebagai suatu perbandingan terhadap semangat, model, atau
institusi hukum dari sistem hukum yang berbeda, untuk mencari
solusi terhadap berbagai persoalan hukum serupa yang terjadi di
berbagai sistem hukum.218
Roger Cotterel menyebutkan bahwa pada prinsipnya
perbandingan hukum tidak hanya sebatas pada hukum doktrinal saja,
akan tetapi juga dapat berfokus pada fungsi hukum dan perubahan-
perubahan sosial. Hal tersebut ditulis dalam buku Law, Culture and
Society sebagai berikut.219
Because the focus of comparative law is not restricted to the law
of any nation state it is better fitted than other doctrinal legal
studies to take full account of the dynamics of social change
represented by the conflicts of globalization and localization.
Comparative law’s long-professed but still inchoate relationship
with legal sociology can be exploited and developed to enable it
to observe and interpret the changing economic and social
contexts of regulation. Certainly, the epistemological and
ontological problems of comparative law should force it, in
217
Munir Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007,hlm. 1-2. 218
Zweigert Konrad dan Hein Kotz, An introduction to Comparative Law ,Volume I, North
Hollan Publishing Company, Amsterdam, 1977. 219
Roger Cotterell, Law, Culture, and Society : Legal Ideas in The Mirror of Social Theory,
Ashgate, Hampshire, 2006, hlm. 151
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
114
seeking to solve them, to take account of these contexts in
pursuing many, though not all, of its aims. Comparative law’s
commonly adopted focus on legal and social ‘functions’,
‘problems’ or ‘interests’ as bases of comparison ought to point it
towards serious concern with analysis of the social environments
in relation to which legal doctrine must establish its meaning.
For example, comparatists have long recognized that power
relations between nation states can strongly affect legal change220
and legal sociologists have begun to demonstrate some
mechanisms of this infl uence. Indeed, power relations in and
between regulated groups and communities should be a major
focus of attention.
Dalam melakukan suatu perbandingan hukum, metode yang
dipakai adalah adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga
hukum (legal institutions) dari sistem hukum yang satu dengan
lembaga hukum, yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang
lain. Dengan membanding-bandingkan itu maka kita dapat
menemukan unsur persamaan, tetapi juga unsur perbedaan dari kedua
sistim hukum itu.221
Perbandingan hukum itu dapat dilakukan baik di
bidang hukum perdata, maupun bidang hukum publik. Bahkan dapat
pula dilakukan dengan membanding-bandingkan suatu lembaga
hukum dimasa yang lampau dengan sifat/corak lembaga hukum yang
sama itu dimasa sekarang.
Johny Ibrahim berpendapat bahwa pendekatan perbandingan
dalam penelitian normatif digunakan untuk membandingkan salah
satu lembaga hukum (legal institutions) dari sistem hukum yang satu
dengan lembaga hukum yang lain. Persamaan-persamaan yang ada
akan menunjukkan inti dari lembaga hukum yang diteliti dan
perbedaan-perbedaan dapat disebabkan oleh perbedaan iklim, suasana
dan sejarah masing-masing bangsa yang bersangkutan.222
Hug telah mengusulkan lima kelompok studi komparatif yang
mungkin bisa digunakan untuk dapat dikelompokkan sebagai hukum
220
H. Gutteridge, Comparative Law 2nd edn, Wildy Reprint, London, 1971, hlm. 160. dalam ibid. 221 Sunarjati Hartono, Capita Selecta Perbandingan Hukum. Alumni, Bandung, 1982, hlm 1 222
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,Bayumedia Publishing,
Jawa Timur, 2006, hlm. 313
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
115
komparatif, antara lain: (1) memperbandingkan sistem asing dengan
sistem domestik dalam rangka menemukan persamaan dan
perbedaan; (2) studi yang menganalisis berbagai solusi secara
obyektif dan sistematis yang ditawarkan oleh berbagai sistem untuk
suatu masalah hukum tertentu; (3) studi yang mengidentifikasi
hubungan kausal antara sistem-sistem hukum berbeda; (4) studi-studi
yang membandingkan tahap-tahap dari beberapa sistem hukum; dan
(5) studi yang berusaha menemukan atau mengkaji evolusi hukum
secara umum berdasarkan sistem dan periodenya.223
Kunci untuk melakukan analisis komparatif yang efektif adalah
dengan mengumpulkan berbagai materi dan informasi yang sesuai
yang memungkingkan para komparatis untuk menempatkan peraturan
hukum atau institusi hukum cabang hukum tertentu pada konteksnya.
Norma-norma dan pola-pola perilaku yang oleh suatu masyarakat
dianggap biasa dan legal mungkin saja dikategorikan sebagai sangat
tidak layak dan tidak dapat diterima oleh masyarakat lainnya.224
Hakikat hukum komparatif adalah pembandingan. Ini berarti
meletakkan unsur-unsur yang dapat diperbandingkan dari dua sistem
hukum atau lebih terhadap satu sama lain dan mementukan
persamaan dan perbedaannya. Sistem hukum dan unsur mana yang
hendak dipilih untuk dibandingkan, dengan sendirinya tergantung
pada tujuan pembandingan itu dan minat-minat pengguna metode
pembandingan.225
Pembandingan dapat bersifat bilateral (diantara dua sistem
hukum) atau multilateral (lebih dari dua sistem hukum).
Pembandingan dapat berupa pembandingan hukum substantif atau
223
Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum (Common Law, Civil Law, dan Socialist Law),
Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 10 diterjemahkan oleh Narulita Yusron dari Peter de Cruz,
Comparative Law in a Changing World, Cavendish Publishing Limited, London-Sidney, 1999. 224
Ibid., hlm 25. 225
Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung,, 2010, hlm
61 diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie dari Michael Bogdan, Comparative Law, Kluwer
and Taxation Publishers, 1994.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
116
pembandingan formal (diantara ciri-ciri formal sistem-sistem hukum,
misalnya, cara menafsirkan undang-undang dan keputusan-keputusan
pengadilan). Lebih jauh lagi ada pembandingan mikro (antara
aturan-aturan hukum individual atau lembaga-lembaga hukum) dan
pembanding makro (antara sistem-sistem hukum secara menyeluruh
atau antara keluarga-keluarga lengkap sistem-sistem hukum).226
Pembandingan mikro pun termasuk membandingkan aturan-aturan
dalam lingkungan hukum dan non hukum.
Unsur sentral dalam perbandingan atau komparatif adalah
pembanding tersebut (the comparison). Pembanding berarti
menghadapkan unsur-unsur yang dapat diperbandingkan dari dua
sistem hukum atau lebih terhadap satu sama lain untuk menemukan
persamaan dan perbedaan diantara sistem-sistem itu.227
Persamaan
dan perbedaan dapat menjadi subyek untuk studi lanjutan mengenai
karaktek teoritis. Penjelasan persamaan dan perbedaan yang
ditemukan dapat menambah pemahaman pengguna metode
pembandingan (comparist) akan hukum negaranya sendiri. Evaluasi
komparatif dari berbagai negara terkait dengan isu yang sama akan
sangat bermanfaat untuk pembuatan draft legislasi atau pekerjaan de
lege ferenda lainnya.228
Salah satu tugas hukum komparatif yang paling menarik dan
paling penting ialah berupaya menjelaskan persamaan dan perbedaan
seperti itu. Saat mencari penjelasan yang dapat dimengerti itulah akan
diketahui faktor-faktor mana yang memengaruhi strukur,
perkembangan, dan muatan-muatan substantif sistem hukum tersebut:
persamaan dan perbedaan di antara faktor-faktor inilah yang
menciptakan persamaan dan perbedaan di bidang hukum.229
226
Rheinstein, Einfuhrung in die Rectvergleichung,, Munchen, 1974, dikutip dari Michael
Bogdan, ibid, hlm, 62. 227
Michael Bogdan, Op.Cit.,, hlm. 8 228
Ibid, hlm. 9 229
Ibid, hlm. 77.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
117
Persamaan dan perbedaan diantara sistem-sistem hukum adalah
dua sisi mata uang yang sama. Persamaan menunjukkan kurangnya
perbedaan, sementara perbedaan menunjukkan kurangnya persamaan.
Karena itu baik persamaan maupun perbedaan dipengaruhi oleh
faktor-faktor yang sama, walaupun arahnya berlawanan. Misalnya,
jika persamaan-persamaan diantara sistem-sistem ekonomi dianggap
menimbulkan persamaan diantara sistem-sistem hukum, maka
perbedaan diantara sistem-sistem ekonomi harus dianggap turut
menyumbang perbedaan-perbedaan di bidang hukum. Maka
penjelasan tentang persamaan dan perbedaan itu pasti dapat
ditemukan dalam sekumpulan faktor relevan yang sama.230
b. Tujuan Perbandingan Hukum
Menurut Sunarjati Hartono, dengan melakukan perbandingan
hukum akan menghasilkan kesimpulan :231
1) Kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan
cara-cara pengaturan yang sama pula;
2) Kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan suasan dan
sejarah menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.
Itulah sebabnya, antara dua sisem hukum mungkin terdapat
persamaan-persamaan (karena adanya kebutuhan yang universal itu),
dan mungkin pula terdapat perbedaan-perbedaan (yang disebabkan
oleh perbedaan suasana dan sejarah).232
Konsekuensi logis studi perbandingan hukum akan membawa
seorang Penulis pada sejarah hukum233
, sebagaimana yang dikatakan
230
Ibid, hlm. 78 231
Sunarjati Hartono. 1982. Op.Cit. hlm 2 232
Ibid. 233
Sejarah mempelajari perjalanan waktu masyarakat di dalam totalitasnya, sedangkan sejarah
hukum satu aspek tertentu dari hal itu, yakni hukum. Sejarah hukum merupakan bagian dari
penyelenggaraan sejarah secara integral dengan memfokuskan perhatian pada gejala-gejala
hukum, di mana penulisan secara integral pula mempergunakan hasil-hasil sejarah secarah
hukum sekaligus meredam efek samping yang terpaksa ikut muncul ke permukaan sebagai
akibat peletakan tekanan pada gejala-gejala hukum. Namun tujuan akhir sejarah hukum, yakni
menunjang dan bermuara di dalam penulisan sejarah secara integral tidak boleh melenyapkan
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
118
F. Pringsheim bahwa “comparative law without the history law is an
imposible task”. Perbandingan hukum memiliki dimensi empiris yang
digunakan sebagai alat bantu (hulp wetenschap) dalam analisis dan
eksplanasi hukum. Penelitian normatif dapat dan memanfaatkan hasil-
hasil penelitian ilmu empiris, namun hanya berstatus sebagai imu
bantu sehingga tidak mengubah hakekat ilmu hukum sebagai ilmu
normatif.234
Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kegunaan perbandingan
hukum adalah sebagai berikut :235
1) Memberikan pemahaman tentang persamaan dan perbedaan di antara
pengertian dasar dari berbagai bidang tata hukum.
2) Mempermudah untuk mengadakan keseragaman hukum (unifikasi).
Kepastian hukum dan kesederhanaan hukum
3) Memberikan pegangan atau pedoman tentang keanekawarnaan hukum
yang harus diterapkan.
4) Memberikan bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang
perlu dikembangkan atau dihapuskan berangsur-angsur demi integrasi
masyarakat.
5) Memberikan bahan tentang hal-hal apa yang diperlukan untuk
mengembangkan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang dimana
kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan.
6) Untuk memecahkan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat, jadi
bukan hanya sekedar menemukan persamaan atau dan/atau
perbedaannya saja.
tujuan parsiil yang spesifik dan perlu ada dari disiplin ini (dari permukaan), yakni penemuan
dalil-dalil dan kecenderungan-kecenderungan perkembangan hukum.
Lihat. John Gilissen & Frits Gorle. Sejarah Hukum: Suatu Pengantar. Refika Aditama,
Bandung, hlm. 11-12. Edisi terjemahan dari : Historiche Inleiding tot het brecht. Kluwer
Rechtswetenschappen-Anwerpent. Belgium. 1991 oleh Freddy Tengker. 234
Ibid, Hlm. 314 235
Soerjono Soekanto, Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung, 1979, Hlm. 1 dalam Munir
Fuady, Op.Cit, hlm. 21.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
119
7) Memberikan kemungkinan untuk mengadakan pendekatan fungsional,
yakni pendekatan dari sudut masalah hukum yang dihadapi dengan
terlebih dahulu menemukan hakikatnya.
8) Mendapatkan bahan untuk dianalisis tentang motif-motif politis,
ekonomi, sosial dan psikologis yang menjadi latar belakang suatu
aturan, traktat, kebiasaan dan yurisprudensi.
9) Berguna bagi pelaksanaan pembaharuan hukum.
10) Untuk mempertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum.
11) Memperluas kemampuan untuk memahami sistem hukum yang ada
serta penegakan hukum yang adil dan tepat.
Perbandingan hukum diterapkan oleh Penulis dengan membandingkan
UU Kepailitan nasional ( yang banyak mengadopsi hukum kepailitan barat
) dan hukum kepailitan Islam serta hukum kepailitan di Negara Arab Saudi
(Saudi Arabia Bankruptcy Law - Saudi Arabia Cabinet Decision No.
264/1439, Royal Decree No. M.5/1439 tanggal 28/05/1439 H atau
13/02/2018). Negara Arab Saudi dipilih karena selain merupakan salah
satu negara Islam terbesar juga memiliki Undang-Undang Kepailitan yang
relatif baru dibentuk (perubahan).
Pembandingan antara hukum kepailitan Islam dengan UU Kepailitan
yang bernuansa hukum barat (civil law) menurut Penulis merupakan suatu
hal yang penting dilakukan, hal tersebut Penulis angkat dari pemikiran Siti
Anisah yang berpendapat bahwa sedikitnya terdapat tiga alasan, antara
lain adanya persinggugan antara hukum kepailitan Islam dengan hukum
kepailitan barat, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan
berkembangannya ekonomi syariah di Indonesia.236
Siti Anisah, dalam disertasinya yang berjudul Perlindungan
Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia,
mengemukakan bahwa perbedaan antara hukum kepailitan Islam dan Barat
antara lain meninggalnya debitor dapat mempercepat jatuh tempo utang-
236
Siti Anisah, Op.Cit. 390.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
120
utang yang dimilikinya, dan pernyataan pailit terhadap debitor dapat
mempengaruhi rencana pernikahannya.
Berkaitan dengan meninggalnya debitor pailit, menurut Imam Ibn
Hazm, seseorang yang meninggal dalam keadaan pailit, maka utang-utang
yang pembayarannya diangsur, seketika itu juga harus dilunasi. Sebab,
kematian menyebabkan jatuh tempo utang pelunasaannya dengan
angsuran dan ditangguhkan itu menjadi gugur karena gugur atau hilangnya
tanggungan bagi orang yang meninggal. Sumber hukumnya adalah firman
Allah yang menyatakan : “... (turun waris hanya dapat terjadi) setelah
ditunaikannya wasiat dan pelunasan utang-utang orang yang meninggal.”
Akibatnya, tidak ada pewarisan kecuali setelah ditunaikannya wasiat dan
pelunasan utang. Dengan demikian wajib hukumnya untuk menghilangkan
beban orang meninggal berupa pembayarann utang itu kepada kreditornya
dan wasita kepada orang yang berhak menerimanya sesuai wasiat. Setelah
itu, sisa harta yang dipergunakan untuk menunaikan wasiat dan melunasi
hutang diberikan kepada ahli waris.237
.
Menurut mazhab Hambali, jatuh tempo pelunasan piutang kreditor
akibat meninggalnya debitor di dasarkan kepada dua riwayat.238
Pertama,
utang yang pelunasannya ditangguhkan dan dibayar secara angsuran tidak
langsung jatuh tempo karena meninggalnya debitor, sebagaimana
Rasullulah bersabda : “Barang siapa meninggal dan meninggalkan hak
juga harta, maka hak dan harta itu adalah untuk para ahli warisnya.”
Tempo pelunasan hutang adalah hak almarhum sehingga hak tersebut
berpindah dari almarhum kepada ahli warisnya. Ketentuan ini berlaku
hanya jika para hali waris percaya dengan kreditor. Apabila ahli waris
tidak mempercayainya, maka jatuh tempo pelunaan hutangnya saat itu.
Kecuali apabila almarhum tidak meninggalkan satu harta pun bagi ahli
237
Al-Mawardi, Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn abb, Al-Muhalla, juz 8, hal. 171, dalam
Siti Anisah, Op. Cit, hlm. 455. 238 Ahmad Azam Othman, The Concept of Bankruptcy (Al-Iflas Under Islamic Law : A
Comparison with English and Malaysian Personal Bankruptcy Laws, Lampeter, University of
Wales, 2000, hlm. 61. Dalam Siti Anisah, Op.Cit. hlm. 455.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
121
waris, maka jatuh tempo pelunasannya terjadi saat itu juga, meskipn Imam
(penguasa) membebankannya kepada kreditor. Hal ini perlu agar para
kreditor tidak “menghilangkan sendiri” hak mereka. Selain itu,
meninggalnya seseorang merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak
menjadikan hak-hak mereka batal, tetapi menjadi batas waktu pengganti
dan petunjuk bagi ahli waris. Menurut Hanabilah, apa yang telah
dikemukakan oleh mereka yang berselisih pendapat dalam hal jatuhnya
tempo pelunasan utang akibat kematian, ditetapkan hukum mengenainya
dengan pertimbangan mashlahah mursalah, tidak dipandang dalam sudut
pandang syarak.239
Dengan pertimbangan ini, maka status utang
tetapmenjadi tanggungan almarhum sebagaimana seharusnya. Utang
tersebut dapat dikaitkan dengan barang atau harta milik debitor (yang
meninggal dunia) sebagaimana berkaitannya hak-hak kreditor atas harta
seorang muflis yang mendapatkan putusan hajr.
Menurut mazhab Hambali, apabila ahli waris lebih tertarik untuk
melunasi utang dan kewajiban yang dibebankan kepadanya untuk kreditor,
atau membelanjakan harta tersebut, maka hal semacam itu tidak boleh
dilakukan. Kecuali apabila kreditor rela, atau diperjanjikan hak nya dalam
sebuaah akta tertulis perihal penanggungan di mana para ahli waris
bersedia untuk menunaikannya, atau pegadaian yang juga dengan akta
tertulis untuk dapat ditunaikannya hak piutang kreditor. Namun,
adakalanya para ahli waris tidak cukup mampu, sedangkan kreditor tidak
rela apabila haknya tidak ditunaikan oleh ahli waris, sehingga hak piutang
kreditor itu harus tetap ditunaikan, meskipun diundur sesuai dengan masa
jatuh tempo yang telah disepakati oleh kreditor dan debitor.
Kedua, pelunasan utang langsung jatuh tempo akibat
kematian.Pendapat itu dikemukakan oleh as-Syabi’i, an-Nakha’i, Suwar,
Malik, ats-Tsauri, as-Syafi’i, dan beberapa ahli hukum Islam. Ahli waris
harus mengikhlaskan harta peninggalan pewaris untuk memenuhi utang
dari kreditor yang piutangnya berupa piutang yang pembayarannya
239
ibid
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
122
bertempo dan diangsung, maupun utang dari kreditor lain yang tidak
diangsur.
Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat tidak dapat ditemukan
ketentuan yang sama dengan hukum kepailitan Islam sebagaimana
dipaparkan sebelumnya. Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat
mengatur hal-hal yang berkaitan dengan meninggalnya seorang debitor
yang dalam proses kepailitan dan bagaimana pembagian harta pailit
kepada para kreditor serta pembagian warisan dari bagian harta kekayaan
debitor melalui putusan pengadilan.
Meninggalnya seorang debitor tidak menghentikan kasus kepailitan.
Alasannya adalah permohonan pernyataan pailit menimbulkan suatu hak
atas semua kepentingan yang sah dan wajar terhadap harta kekayaan
debitor. Setelah adanya putusan pailit, terdapat dua hal yang berbeda
berkaitan dengan harta kekayaan debitor: harta pailit, dan harta yang
dikecualikan dari harta pailit. Pengadilan mempunyai kewenangan ekslusif
berkaitan dengan harta pailit, dan kematian debitor tidak menyebabkan
pengadilan kehilangan kewenangan tersebut.240
Berkaitan dengan rencana perkawinan, dalam hukum Islam,
pernyataan pailit terhadap debitor ternyata mempengaruhi rencana
perkawinan debitor, baik rencana perkawinan atau pun perceraian yang
akan dilakukan oleh debitor. Sebagian besar ahli hukum Islam
memperbolehkan pernikahan, namun melarang debitor untuk membayar
mahar, karena akan mengurangi harta paiit yang seharusnya dibagikan
kepada para kreditor.
Mazhab Maliki memperbolehkan pernikahan, namun melarangnya
membayar mahar dari bagian harta yang dibagi yang diterima oleh debitor
setelah adanya pernyataan pailit.241
Namin demikian, Mazhab Maliki juga
memiliki pandangan lain, yaitu pernikahan yang dilakukan setelah adanya
240
David B. Young, “The Intersection of Bankruptcy and Probate,” 49 S. Tex L. Rev. 351,
20117, hlm. 367-368, dalam Siti Anisah, Op.Cit, hlm. 457 241
Malik Anas, Al-Mudawwanah al-Khubra wa ma’aha Muqaddimat ibn Rushd, vol.4, Dar al-
Fikr, n.d., hlm. 122 dalam Siti Anisah,Op. Cit. hlm. 459
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
123
pernyataan pailit adalah dilarang. Apabila pernikahan dilakukan pada masa
debitor pailit, maka harta yang diperoleh dari pernikahan itu dapat
merupakan bagian dari harta yang dibagi kepada para kreditor.242
Pandangan yang melarang debitor pailit untuk menikah merupakan
pendapat yang banyak diikuti. Hal ini karena pernikahan dapat dilakukan
oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk menghidupi istrinya,
sebagaimana hadis yang menyatakan : “ Wahai pemuda yang diantara
kamu telah mampu, menikahlah, dengan begitu akan lebih menjaga
pandanganmu dan mencegahmu dari maksiat.”243
Secara relatif, seseorang
yang memiliki masalah keuangan dilarang untuk menikah. Hal ini juga
akan menyebabkan penderitaan bagi suatu atau istri karena
ketidakmampuan debitor pailit untuk mengatur seluruh hartanya.
Diberikannya hak debitor untuk menikah juga berlaku untuk hak-hak
yang lain seperti diperbolehkannya debitor untuk cerai al-khul’, cerai
thalaq mau pun rujuk. Cerai khul diperbolehkan karena debitor pailit
menerima sesuatu atau kompensasi dari istrinya atau diambil dari mahar
istri.244
Pengeluaran suami dapat dikurangi karena suami berkewajiban
untuk melindungi istirnya sebagaimana hadits yang menyatakan :” Nabi
Muhammad telah mengizinkan istrinya ( yang telah dicerainya dengan
cerai khul” yaitu dengan memberikan kompensasi pada suaminya) untuk
tinggal bersama di rumah orang tuanya.245
Hukum ini tidak berlaku pada
istri karena perceraian. Hal ini terjadi dengan memberikan kompesasi
242
Shams al-Din Muhamad ‘Arfah al-Dasuqi, Hashiyyat al-Dasuqi ‘ala Sharh al-Kabir, vol.3, Dar
Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, n.d., hlm. 264. Siti Anisah,Op. Cit. hlm. 459 243 Ahmad Azam Othman, The Concept of Bankruptcy (Al-Iflas Under Islamic Law : A
Comparison with English and Malaysian Personal Bankruptcy Laws, Lampeter, University of
Wales, 2000, hlm. 66. Dalam Siti Anisah, Op.Cit. hlm. 495. 244
Abu Barakat Ahmad ibn Ahmad al-Dardir, Al-Sharh al-Saghir, vol. 3, Daulat al Amariyyah
al-“Arabiyyah al-Muttahidah, 1989, hlm. 352 ; Ahmad ibn Muhammad al-Sawi, Bulghah al-
Salik li Aqrab al-Masalik ila Madhhab al-Imam Malik ‘ala al-Sharh al-Shagir, vol. 2, Dar al-
Ma’rifah, 1988, hlm. 127 dalam Siti Anisah, Op.Cit., hlm. 461. 245
Malik Anas, Al-Muwatta’, (no. 1990), 11th
ed. Dar al-Fikr, n.d., Beirut, hlm. 384-385; Abu
‘Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi’i, Musnad al-Imam al-Syafi’i, 1st ed., Dar al-Rayyan
li al-Turath, Kairo, 1987, hlm. 262-263, dalam Siti Anisah, ibid.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
124
kepada suami yang menyebabkannya menggunakan hartanya. Dengan
begitu, hal ini mengganggu para kreditornya.246
Mazhab Maliki mempunyai pandangan bahwa perceraian dapat
dilakukan, dengan demikian penangguhan pembayaran mahar menjadi
jatuh tempo. Akhirnya, istri membagi mahar yang belu dibayar kepada
para kreditor.
Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat, harta
kekayaan yang diperoleh dalam suatu proses perceraian termasuk sebagai
harta pailit pada saat debitor mengajukan permohonan pailit. Asumsinya
adalah pembagian harta pernikahan akan terjadi sebelum proses kepailitan
selesai.247
Ada pun tujuan perbandingan ini adalah untuk menemukan persamaan
dan perbedaan serta kelebihan dan mungkin kekurangan (bila ada) dalam
sistem hukum tersebut di atas.
B. LANDASAN TEORI
Jan Gijssels dan Mark van Hoecke berpendapat bahwa tugas teori hukum
adalah percobaan mencapai integrasi interdisipliner. Berbeda dengan
dogmatika hukum, teori hukum berupaya untuk menjelaskan hukum secara
mendasar atau dengan kata lain, untuk memberikan jawaban atas pertanyaan
ilmiah “mengapa hukum itu adalah sebagaimana ia adanya”, dengan suatu
penelitian yang tidak membatasi diri, seperti dogmatika hukum, pada apa yang
dapat ditemukan “sesuai dengan hukum” (“in rechte”), melainkan menerobos
lebih dalam sebab maupun motif-motifnya. Sebab-sebab dan motif-motif dari
hukum, telah kami kelompokkan, sebagai faktor-faktor pembentukan hukum,
246 Abu Barakat Ahmad ibn Ahmad al-Dardir, Al-Sharh al-Saghir, vol. 3, Daulat al Amariyyah al-
“Arabiyyah al-Muttahidah, 1989, hlm. 352 ; Ahmad ibn Muhammad al-Sawi, Bulghah al-Salik
li Aqrab al-Masalik ila Madhhab al-Imam Malik ‘ala al-Sharh al-Shagir, vol. 2, Dar al-
Ma’rifah, 1988, hlm. 127 dalam Siti Anisah, ibid.
Wanita yang pailit juga berhak untuk meminta cerai dengan memberikan kompensasi
pada suaminya sama dengan hak wanita untuk menikah, 247
Steven J. Schwartz, “ Marital Dissolution and Bankruptcy: The Rights of the Bankruptcy
Trustee to Administer Community Property and To Avoid and To Recover Property Divisions,
“ 28 Cal. Bankr. J. 523, 2006, hlm. 528 dalam Siti Anisah, Op.Cit., hlm. 462.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
125
ke dalam dua kelompok pengertian yang mengglobal : “keterberian-
keterberian faktual” dan “keyakinan-keyakinan idiil”.248
Menggunakan ilmu hukum sebagai salah satu ilmu sosial, maka teori
hukum juga merupakan bagian dari teori sosial yang diperlukan supaya ilmu
tersebut dapat berkembang. Mengenai hal tersebut, Bryan S. Turner
menyebutkan, “Social theory provides the necessary analytical and
philosophical framework withinwhich the social sciences can develop. Social
theory both sustains the achievementsof the past, notes the needs and
limitations of the present, and points the way tofuture research issues and
questions.”249
Sedangkan M.A. Loth berpendapat bahwa teori hukum itu menyibukkan
diri dengan hubungan antara hukum dan logika. Selain itu, teori hukum juga
menyibukkan diri dengan metodologi. Ia menyangkut dua aspek. Teori hukum
meneliti objek dan metode di satu pihak dari ilmu hukum (teoretikal) dan di
pihak lain dari pengembangan hukum (praktikal) seperti perundang-undangan
dan peradilan. Jadi, pada satu sisi, teori hukum itu mengandung filsafat ilmu
dari ilmu hukum. Pada sisi lain, teori hukum itu adalah suatu “ajaran metode”
untuk praktek hukum. Di dalamnya ia mengarahkan perhatiannya pada
pembentukan hukum (perundang-undangan) dan penemuan hukum (ajaran
interprestasi). Ajaran metode ini dalam penerbitan yang lalu dari buku ini
ditunjuk dengan istilah “kesenian hukum” (rechtkunst).250
Golding menjelaskan perbedaan antara filsafat ilmu dengan teori hukum.
Filsafat ilmu menekankan pembahasan sebagian besar dari sudut studi filsafat,
dan oleh karena itu menekankan penelitian dan penyelidikan dari sudut tradisi
filsafat. Sedangkan teori hukum cenderung kepada bentuk operasional
berdasarkan legal academy, yang cenderung mengkonsentrasikan diri kepada
248 Jan Gijssels dan Mark van Hoecke ( diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta), Apakah Teori
Hukum itu ? (Penerbitan Tidak Berkala No.3), Laboratorium Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 26. 249 Bryan S. Turner (editor), The New Blackwell Companion to Social Theory, Blackwell, West-
Sussex, 2009, hlm. 1. 250 B. Arief Sidharta (Penerjemah), Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori
Hukum, dan Filsafat Hukum, (Cetakan Keempat) Refika Utama, Bandung, 2013, hlm.29.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
126
rasionalisasi dan legitimasi dari legal doctrine seperti perbuatan melawan
hukum dan kontrak. Tentu dalam pembahasan filsafat hukum tidak dapat
dihindarkan membicarakan teori hukum yang bersumber dari filsafat
hukum.251
Selanjutnya, Golding menjelaskan teori hukum sekadar memberikan
deskripsi (informasi) yang positif teoritikal, sama sekali tidak melakukan
penilaian normatif (baik -buruk). Hal tersebut serupa dengan yang
disampaikan oleh, Aleksander Peczenik, “In general, law theorists say many
things, but it is not always clear what they talk about, and even less clear
why.”252
Ian McLeod juga memiliki pendapat yang sama,”One immediately
apparent difference is that legal theory is painted on a larger canvas; or, to
change the metaphor into a more appropriately verbal one, it asks bigger
questions. ... In a nutshell, therefore, legal theory involves a progression from
the study of laws to the study of law.253
Teori hukum dengan demikian berfungsi untuk mengolah produk dari
ilmu- ilmu lain yang juga berobjekkan hukum, lalu mengubahnya menjadi
teknik hukum untuk kepentingan ilmu hukum. Di samping itu, teori hukum
melakukan pembentukan, pengolahan, pengembangan, dan pemantapan
(pembakuan) konsep-konsep yuridis. Sebagai disiplin hukum yang berada di
antara tingkat abstraksi ilmu hukum dan filsafat hukum, maka teori hukum
juga difungsikan untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan
diajukan kepada filsafat hukum. Sebaliknya, jawaban-jawaban yang diberikan
filsafat hukum merupakan porsi teori hukum untuk kembali mengolahnya
secara deskriptif.254
251
Martin P. Golding and William A. Edmundson (Eds), Philosophy of Law and Legal Theory,
Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 2005, dalam Sobirin Malian, Perkembangan Filsafat Ilmu
Serta Kaitannya dengan Teori Hukum, Jurnal UNISIA, Vol. XXXIII No. 73 Juli 2010, hlm. 67 252 Aleksander Peczenik, Theory Choice in Jurisprudence, Stockholm Institute for Scandianvian
Law 1957-2010, hlm. 292. 253 Ian McLeod, Legal Theory, Macmillan, London, 1999, hlm.2 254 Ibid.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
127
Edy Faishal Muttaqin menyebutkan eksistensi ilmu hukum ditinjau dari
filsafat ilmu mencakup 3 (tiga) landasan pengembangan, yaitu :255
1) Ontologi, obyek kajian dalam ilmu hukum adalah norma-norma, seperti,
norma perilaku dan norma kewenangan, termasuk norma-norma yang
telah hidup secara turun-temurun dalam masyarakat. Dalam hubungan
antara subyek dengan obyek, posisi subyek berada di luar obyek sebagai
pemerhati (touschouwer).
2) Epistemologi, metodologi yang dipergunakan adalah secara induksi dan
deduksi, dengan criteria kebenaran secara preskriptif atau seyogianya.
3) Aksiologi, ilmu hukum dalam pengembangannya memiliki manfaat
berupa penyelesaian terhadap semua masalah hukum konkret
(problemsolving) yang terjadi dalam masyarakat. Pengembangan Ilmu
Hukum bertujuan untuk menciptakan, menjaga dan mengendalikan
keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan manusia. Sedangkan
relevansi Ilmu Hukum dengan nilai adalah hukum merupakan nilai,
sehingga Ilmu Hukum kemudian merumuskan dan menerapkan nilai-nilai
tersebut.
Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan, teori lingkar konsentris, teori
kepastian hukum, teori penyelesaian sengketa dan teori kewenangan, sebagai
berikut.
1. Teori Lingkar Konsentris.
Teori lingkar konsentris dikembangkan oleh H.M. Tahir Azhary.
Teori ini menggambarkan hubungan erat antara agama, hukum dan
negara. Ketiga komponen ini apabila disatukan akan membentuk
lingkaran konsentris yang merupakan satu kesatuan dan berkaitan erat
antara yang satu dengan yang lain. Agama sebagai komponen pertama
berada pada posisi lingkaran terdalam, karena merupakan inti dari
lingkaran tersebut, baru kemudian disusul hukum pada lingkaran kedua
dan lingkaran berikutnya adalah negara. Teori ini digunakan untuk
255 Edy Faishal Muttaqin, Eksistensi Ilmu Hukum Terhadap Ilmu-Ilmu Lain Ditinjau dari Filsafat
Ilmu, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus 2010, hlm. 5
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
128
menjelaskan hukum Islam dalam kaitannya dengan hukum nasional
Republik Indonesia. Negara dan hukum Islam merupakan produk atau
bagian (derivasi) dari Agama Islam itu sendiri. Ketiganya adalah satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.256
Menurut teori ini, agama, hukum, dan negara apabila disatukan akan
membentuk lingkaran konsentris yang merupakan suatu kesatuan dan
berkaitan erat satu dengan lainnya. Antar ketiganya membentuk relasi
yang saling berhubungan. Agama berada pada posisi lingkaran pertama
yang terdalam menunjukkan pengaruh agama sangat besar sekali terhadap
hukum yang berada pada lingkaran kedua sekaligus pula, agama
merupakan sumber utama dari hukum disamping rasio sebagai
pertimbangan komplementer. Ditinjau dari perspektif kaidah-kaidah “al-
din al-Islami” yang terdiri dari tiga komponen, yaitu akidah dengan tauhid
(Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagai titik sentral, syariah dan akhlak
harus tercermin dalam struktur dan substansi hukum, sehingga konsep
hukum dalam lingkungan itu berisi, bukan hanya semata-mata hukum
dalam arti normatif saja, tetapi juga hukum dan kesusilaan.
Negara sebagai komponen ketiga berada dalam lingkaran
terakhir.Tegasnya posisi negara pada lingkaran ketiga setelah hukum
dimaksudkan dalam teori lingkaran konsentris ini, negara mencakup kedua
komponen yang terdahulu yakni agama dan hukum.257
Karena agama
merupakan inti dari lingkaran konsentris ini, maka pengaruh dan peran
agama sangat besar sekali terhadap hukum dan negara. Dengan gambaran
ini, sekaligus pula memperlihatkan betapa eratnya hubungan antara agama,
hukum dan negara, karena komponen-komponen itu berada dalam satu
kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan. Perlu ditegaskan, bahwa harus
256
Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat
dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,
Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 67. 257
Abdul Chair Ramadhan, Teori Solvanisasi Hukum: Mempertemukan Kepentingan Agama dan
Negara. https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2017/06/19/118861/teori-
solvanisasi-hukum-mempertemukan-kepentingan-agama-dan-negara.html, diakses 28
September 2019.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
129
dipahami kalau negara diletakkan pada lingkaran yang terakhir, maka hal
itu tidak berarti negara “mengungkung” atau “mengurung” hukum
agama.258
Muhammad Tahir Azhary menggambarkan diagram teori lingkaran
konsentris sebagai berikut.
Teori lingkar konsentris digunakan Penulis untuk melakukan analisa
kompetensi absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara kepailitan di
bidang ekonomi syariah antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga
dalam perspektif persaingan hukum antara hukum Islam dan hukum Barat.
2. Teori Kepastian Hukum.
Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban (order).
Tujuan tersebut sejalan dengan fungsi utama hukum, yaitu mengatur.
Ketertiban merupakan syarat dasar bagi adanya suatu masyarakat.
Kebutuhan akan ketertiban merupakan fakta dan kebutuhan objektif bagi
setiap masyarakat manusia. Para penganut teori hukum positif
menyatakan ‘kepastian hukum’ sebagai tujuan hukum, dimana ketertiban
atau keteraturan, tidak mungkin terwujud tanpa adanya garis-garis
perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada
kepastian dan untuk adanya kepastian hukum harus dibuat bentuk yang
pasti pula (tertulis).259
Terkait dengan pembentukan hukum tertulis yang
258
Muhammad Tahir Azhary, Loc. Cit., hlm.68 259 Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya,
Bandung, 1993, hlm. 22 dalam Zulfi Diane Zaini, Perspektif Hukum Sebagai Landasan
Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat), Jurnal Hukum, Vol XXVIII,
No. 2, Desember 2012, hlm. 391.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
130
menjamin kepastian hukum pada masa kini, Wojciech Cyrul berpendapat
bahwa fokus hasil pembentukan undang-undang adalah kepada kualitas
teks undang-undang tersebut. Secara lebih jelas, Wojciech Cyrul
menerangkan sebagai berikut.
”As we can see, contemporary reflection on lawmaking to much
extent is focused on the outcome of lawmaking: the quality of legal
texts. Therefore, the final decision on the selection of optimal
regulation depends both on the costs and effectiveness of the specific
solution as well as on its compatibility with already binding legal
texts.”260
Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum
yang dikemukakan oleh L.A. Hart dikombinasikan dengan teori Gustav
Radbruch. H.L.A Hart memecah hukum (dalam hal ini adalah hukum
positif ) menjadi dua bagian. Pertama, primary rules yaitu aturan-aturan
hukum yang secara langsung memberikan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban kepada orang per orang. Aturan-aturan itu meliputi hukum
perdata dan hukum pidana. Kedua, secondary rules, yaitu aturan-aturan
hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada penguasa negara.261
Hart mengatakan oleh karena hukum harus konkret maka harus ada
pihak yang menuliskan. Pengertian ‘yang menuliskan’ itu menunjuk
pengertian bahwa hukum harus dikeluarkan oleh suatu pribadi ( subjek )
yang mempunyai otoritas untuk menerbitkan dan menuliskannya. Otoritas
tersebut adalah negara. otoritas negara ditunjukkan dengan adanya atribut
negara, berupa kedaulatan negara. berdasarkan kedaulatannya, secara
internal negara berwenang untuk mengeluarkan dan memberlakukan apa
yang disebut sebagai hukum positif. Selanjutnya Hart menyatakan
“pertama, hukum ( yang sudah dikonkretisasi dalam bentuk hukum
positif) harus mengandung perintah “ dan kedua, tidak selalu harus ada
kaitan antara hukum dengan moral dan dibedakan dengan hukum yang
260 Luc J. Wingents (editor), Legislation in Context: Essays in Legisprudence, Ashgate,
Hampshire, 2007, hlm. 43 261 FX. Adji Samekto, Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal,
Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1 Januari 2012, hlm. 81. Lihat juga : Torben Spaak,
Kelsen and Hart on the Normativity of Law, Stockholm Institute for Scandianvian Law 1957-
2010, hlm. 408.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
131
seharusnya diciptakan ( there is no necessary connection between law and
morals or law as it ought to be).262
Meminjam pendapat HLA Hart
tersebut Penulis berpendapat bahwa sudah sangat tepat apabila negara
memberikan perintah melalui Undang-Undang yang memerintahkan
penyelesaian perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah melalui
Pengadilan Niaga Syariah yang berkedudukan di lingkungan peradilan
agama.
Hart, dalam melihat hukum, memposisikan diri sebagai social
observer of law. Hart menjelaskan hukum dari pandangan eksternal agar
terbebas dari bias dan inward looking.263
Kepastian hukum dalam the
concept of law karya H.L.A. Hart mengomentari kepastian hukum dalam
undang-undang.264
Beliau berpendapat bahwa kadang-kadang kata-kata
dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang
tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang
mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu
262 FX. Adji Samekto, Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal,
Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1 Januari 2012, hlm. 80 263
Achmad Gunaryo, “Beberapa Catatan tentang Konsep Hukum HLA Hart dalam Buku The
Concept of Law,dimuat dalam Jurnal Hukum Progresif, Vol.3, No. 1. Tahun 2007 (online)
dalam Adji Samekto, Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme,
KONpres, Jakarta, 2015, hlm. 83.
Inti dari deskripsi Hart tentang hukum dan sistem hukum adalah sebagai berikut.
At the core of Hart’s description of law and the legal system is the existence of
fundamental rules accepted by officials as stipulating these law-making procedures. In
particular, the ‘rule of recognition’ which is the essential constitutional rule of a legal system,
acknowledged by those officials who administer the law as specifying the conditions or criteria
of legal validity which certify whether or not a rule is indeed a rule.
Lihat : Raymond Wack, Understanding Jurisprudence: An Introduction of Legal Theory (Third
Edition) , Oxford University Press, New York, 2012, hlm. 80
264
Mengenai kepastian hukum, Jimly Assidiqie berpendapat bahwa fungsi utama hukum dapat
dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sebagai instrumen yang mengatur dan membatasi
(limitating function) sehingga dapat diwujudkan adanya kepastian (legal certainty) dan
keadilan (justice) bagi setiap individu, tetapi dapat pula dilihat sebagai instrumen yang
membebaskan (liberating function) sehingga dapat diwujudkan adanya struktur sosial yang adil
dan pasti yang bebas dari penindasan dan kekerasan struktural.
Lihat : Komisi Yudisial Republik Indonesia, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia (
Bunga Rampai ), Sekretariat Jenderal Komis Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.
20
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
132
terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum
lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidakpastian
(legal uncertainty) hukum.265
Bagi Hart, hubungan bahasa dan hukum
memiliki posisi yang penting dan menjadi suatu hal yang layak diberikan
perhatian lebih.
Hart berpendapat mengenai sebuah bahasa dalam hukum sebagai
berikut.
“ ... we cannot properly understand law unless we understand the
conceptual context in which it emerges and develops. He argues, for
instance, that language has an ‘open texture’: words (and hence
rules) have a number of clear meanings, but there are always several
‘penumbral’ cases where it is uncertain whether the word applies or
not.”266
Sebagaimana dikutip oleh Torben Spaak, Gustav Radbruch lebih
mengutamakan kepastian hukum (legal certainty) daripada keadilan dan
kepastian.267
“Radbruch also reckons with a third element of the idea of law, in
addition to justice and expediency, namely legal certainty
(Rechtssicherheit). We need legal certainty, he explains, because there
is no non-relativistic answer to the question ‘‘justice or expediency?’’.
It is more important that the strife of legal views be ended than that
it be determined justly and expediently. The existence of a legal order
is more important than its justice and expediency, which constitute the
second great task of law, while the first, equally approved by all, is
legal certainty, that is, order, or peace.”
Demikian pula dengan Reza Banakar, mengutip pendapat Gustav
Radbruch bahwa tidak akan terwujud keadilan tanpa tatanan sosial.
Keadilan merupakan inti dari nilai hukum, akan tetapi supaya terwujud
keadilan, tatanan sosial harus diprioritaskan. Secara lebih jelas, Reza
Banakar menyatakan sebagai berikut.
265
Lihat : H.L.A Hart, The Concept of Law, Clarendon Press-Oxford, New York, 1997
diterjemahkan oleh M. Khozim,Konsep Hukum, Nusamedia, Bandung, 2010, hal. 230 266
Raymond Wack, Loc. Cit. hlm. 80 267 Torben Spaak, Meta-Ethic and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch, Springer :Law
and Philosophy, 28, 2009, hlm. 269
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
133
According to Radbruch, when conflict arises between the principle
of justice and positive law, the court should maintain legal certainty
and security (ultimately opting for social order) by applying the rules
of law, even when their application results in injustice. The logic
underpinning this position is deceptively simple: there can be no
justice without social order. For Radbruch justice is the core value of
law, which means that positive law cannot be granted total primacy
over the requirement of justice and yet, paradoxically, social order
must be prioritised if justice is to be realised.268
Demikian pula dengan Brian Brix, menyatakan bahwa Gustav
Radbruch lebih menekankan kepada kepastian hukum, sebagai berikut.269
In those writings, Radbruch seemed to assert that it was the third
element, legal certainty, which was the most important, at least
within the idea of law: "It is more important that the strife of legal
views be ended than that it be determined justly and expediently.
The existence of a legal order is more important than its justice
and expediency”
Robert Alexy juga mengutip hal yang sama dari terkait sikap Gustav
Radbruch yang lebih mengutamakan kepastian hukum tersebut diatas,
akan tetapi jika undang-undangnya cacat maka terjadi pengecualian
sebagai berikut.
‘the positive law, secured by legislation and power, takes
precedence even when its content is unjust and fails to benefit the
people, unless the conflict between statute and justice reaches such
an intolerable degree that the statute, as “flawed law,” must yield
to justice.270
Sedangkan dalam konteks pembentukan Undang-Undang,
Darmodiharjo berpendapat bahwa hukum di bentuk karena pertimbangan
keadilan (gerechtigkeit) disamping sebagai kepastian hukum
(rechtssicherheit) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit).271
268 Reza Banakar, Normativity in Legal Sociology : Methodological Refl ections on Law and
Regulation in Late Modernity, Springer, London, 2015, hlm. 63. 269
Brian Bix, Radbruch Formula and Conceptual Analysis, The American Journal of
Jurisprudence Vol. 56, 2011, hlm. 47 270
Radbruch, Gustav. 2006. Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law. Trans. Bonnie
Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson. Oxford Journal of Legal Studies 26, 2006, 7, (1st
ed. in German 1946.) dalam Robert Alexy, On The Concept and the Nature of Law, Ratio
Juris. Vol. 21 No. 3 September 2008, hlm. 282. 271
Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana
Filsafat Hukum Indonesia), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 5
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
134
Terkait dengan kepastian hukum, Mochtar Kusumaatmadja
mengemukakan bahwa tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal
saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya
masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan
yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya.
Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian
hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin
manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan
Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan
ketertiban.272
Dalam konteks kepastian hukum dan peradilan, Frans
Magnis Suseno berpendapat bahwa kepastian hukum berarti norma-norma
hukum yang telah diundangkan oleh negara dilaksanakan dengan
konsisten sesuai dengan rumusan hukum normatif hukum tersebut.
Kepastian hukum menghendaki pengadilan sebagai institusi negara dalam
mengambil keputusan terhadap suatu perkara, senantiasa mengedepankan
norma-norma hukum yang mengaturnya.273
Selanjutnya, Gustav Radburch274
berpendapat bahwa ada dua
pengertian tentang kepastian hukum di negara berkembang yaitu
kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum.
Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum.
Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-
272 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional,
Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 13. 273 Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Modal Dasar Kenegaraan Modern,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 100 dalam Harjono, Konsistensi Hakim
Pengadilan Niaga dalam Mengadili Perkara Kepailitan dengan Klausula Arbitrase, Yustisia
Edisi Nomor 65 April-Juni 2004 hlm. 835 274
Gustav Radbruch terkenal dengan 3 formula nilai hukum yaitu kepastian, keadilan dan
kemanfaatan sebagaimana dijelaskan oleh F. Saliger bahwa kepastian hukum cenderung
berkonflik dengan keadilan :
The formula’s statement in fact is threefold: First of all that the conflict of justice and
legal certainty (Rechtssicherheit) could not be solved absolutely, thus allowing only a
conditional priority. Secondly, that this conditional priority operates in favor of legal
certainty; thirdly, that the primacy of legal certainty is revoked, when injustice becomes
intolerable (unerträglicher Gerechtigkeitsverstoß).
Lihat : F. Saliger, Content and Practical Significance of Radbruch’s Formula, КЛАСИКИ
ФІЛОСОФІЇ ПРАВА: ГУСТАВ РАДБРУХ, Vol. 2, 2004, hlm.68
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
135
hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan
kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-
banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak
ada ketentuan yang saling bertentangan (undang-undang berdasarkan pada
sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan
kenyataan hukum (rechtswerkelijheid) dan undang-undang tersebut tidak
ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.275
Mark Fenwick and Stefan Wrbka berpendapat bahwa dalam konteks
modernitas hukum, prinsip kepastian hukum – gagasan bahwa hukum
harus cukup jelas untuk memberi mereka norma-norma hukum dengan
sarana untuk mengatur perilaku mereka sendiri dan untuk melindungi
terhadap pelaksanaan sewenang-wenang kekuasaan publik – telah
beroperasi sebagai nilai dasar aturan hukum. Selama beberapa dekade
terakhir, kepastian hukum semakin mendapat tekanan dari sejumlah
tuntutan yang saling bersaing yang dibuat oleh hukum kontemporer,
khususnya tuntutan agar hukum tersebut lebih fleksibel dan responsif
terhadap lingkungan sosial yang ditandai oleh perubahan ekonomi, sosial,
dan teknologi yang pesat. Secara khusus, harapan bahwa hukum
beroperasi dalam konteks transnasional baru dan mengatur ruang lingkup
kehidupan sosial yang semakin meluas telah menciptakan tingkat
ketidakpastian baru tentang kepastian hukum.276
Jan Michiel Otto berpendapat bahwa kepastian hukum nyata
sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun
sekaligus lebih dari itu. Jan Michiel Otto mendefinisikannya sebagai
kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:
a) tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah
diperoleh (accessible), diterbitkan oleh atau diakui karena
(kekuasaan) negara;
275
E. Utrecht, 1959, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Cetakan Keenam,) Penerbit Balai Buku
Ichtiar, Jakarta, 1959, hlm. 26 276 Mark Fenwick & Stefan Wrebka, Legal Certainty in a Contemporary Context, Springer,
Singapore, 2016, hlm. 1-2.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
136
b) bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum
itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
c) bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga-
negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku
mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
d) bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
(independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum
tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa
hukum yang dibawa kehadapan mereka;
e) bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.277
Berdasarkan teori kepastian hukum sebagaimana tersebut diatas,
selain untuk mengkaji validitas norma dan kepastian hukum mengenai
kompetensi absolut pengadilan niaga maupun pengadilan agama dalam
memeriksa dan memutus perkara kepailitan di bidang ekonomi syari’ah
dengan mengkaji rumusan dari pasal-pasal undang-undang terkait. Tujuan
utama dari penerapan teori kepastian hukum adalah untuk mengetahui
apakah di dalam kedua undang-undang yang mengatur tentang
kewenangan untuk memeriksa perkara kepailitan di bidang ekonomi
syari’ah yaitu Undang-Undang Kepailitan untuk Pengadilan Niaga
maupun Pengadilan Agama yaitu UU No. 3/2006 jo. UU No. 50/2009
secara jelas dan pasti.
3. Teori Penyelesaian Sengketa.
Thomas J. Miceli menyebutkan bahwa ada tiga alasan para ekonom
atau pelaku bisnis menyukai penyelesaian sengketa melalui jalur hukum
salah satunya adalah teori-teori ekonomi dapat berguna untuk
menjelaskan dan memberikan prediksi bagaimana para pihak secara
rasional akan menyelesaikan masalahnya dan dapat menawarkan saran
277 Adriaan E. Bedner, dkk (editor), Kajian Sosio Legal : Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan
Negara Hukum, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 122.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
137
untuk menurunkan biaya persidangan. Secara lebih lengkap, Thomas J.
Miceli menyatakan sebagai berikut.278
First, the manner in which they are resolved has an important effect
on the cost of operating the legal system. Second, economic theory is
useful in explaining and predicting how rational litigants will resolve
disputes and can therefore offer suggestions for lowering the cost of
litigation. Finally, the manner in which parties resolve disputes has
implications for the structure of legal rules, which in. turn affects
investments in the future by individuals to avoid disputes in the first
place.
Menurut Hoebel, hukum dapat berperan: pertama, merumuskan
hubungan-hubungan di antara anggota masyarakat, mana yang wajib,
haram, mubah dan seterusnya, sebagaimana dalam hukum taklîfî. Kedua,
siapa yang boleh atas kekuasan atas siapa berikut prosedurnya. Ketiga,
penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Keempat,
mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur
kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat apabila keadaan
berubah.279
Lawrence M. Friedman juga menyebutkan bahwa yang
terpenting adalah fungsi dari hukum itu sendiri yaitu sebagai kontrol
sosial (ibarat polisi), penyelesaian sengketa (dispute settlement), skema
distribusi barang dan jasa (good distributing scheme), dan pemeliharaan
sosial (social maintenance).280
Berangkat dari pernyataan Hoebel dan Lawrence M. Friedman
tersebut di atas terutama pada peran penyelesaian konflik atau sengketa,
maka peran hukum dalam menyelesaiakan sengketa harus dioptimalkan
salah satunya adalah dengan mengoptimalkan fungsi dan peran
Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
278 Thomas J. Miceli, Economics of The Law : Tort, Contract, Property, Litigation, Oxford
University Press, Oxford, 1997, hlm. 156 279 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-
Pengalaman di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 35. 280 Lawrence M. Friedman, American Law, An Introduction, W.W. Norton & Company, New
York, 1984, hlm. 5 – 14.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
138
Mather dan Yngvesson menyebutkan, “ a dispute can be defined as a
particular stage of a social relationship in which conflict between two
parties (individuals or groups) is asserted before a third party, who may
be a family member, neighbour, the police, a community organization, an
administrative tribunal or court .”281
Sharyn L. Roach Anleu kemudian menambahkan, “Third parties vary
in their level of independence from the claims being asserted by either
disputant, their role in the management of the dispute and the level of
formality or public accountability that they provide. The third party
usually defines the nature of the dispute and specifies how it should be
resolved or settled.”282
Sengketa adalah salah satu risiko dari transaksi (akad) bisnis,
termasuk bisnis dengan sistem syariah; dan risiko dimaksud berupa ingkar
janji (wanprestasi)/melanggar hukum, atau adanya perbuatan melawan
hukum (onrechmatige daad).283
Wanprestasi diartikan sebagai keadaan pihak (atau pihak-pihak) yang
tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang telah
ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak. Subekti
menjelaskan bahwa wanprestasi (lalai) adalah: a) tidak melakukan apa
yang disanggupi akan dilakukannya; b) melaksanakan apa yang
dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c) melakukan apa
yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau (d) melakukan sesuatu yang
menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.284
Sedangkan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) meliputi:
a) perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku; b) perbuatan
281
Lynn Mather and Barbara Yngvesson, 'Language, Audience, and the Transformation of
Disputes', Law & Society Review Vol. 15, 1980-1981, hlm. 775-82l . 282 Sharyn L. Roach Anleu, Law and Social Change, Sage Publication, London, 2000, hlm. 108 283
Sengketa/perselisihan lahir antara lain karena perbuatan curang dalam berbisnis.
Lihat : Soedjono Dirdjosisworo, Antisipasi terhadap Bisnis Curang: Pengalaman Negara Maju
dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property) dan pengaturan E-
Commerce serta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia, ( cetakan ke 1) CV Utomo,
Bandung, 2005 dalam Jaih Mubarok, Op.Cit., hlm. 4. 284
R. Subekti, Hukum Perjanjian (cetakan ke 20), Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 45.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
139
yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; c) perbuatan
yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; d) perbuatan yang
bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden); atau e) perbuatan yang
bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk
memperhatikan kepentingan orang lain285
Penyelesaian sengketa, secara filosofis merupakan upaya untuk
mengembalikan hubungan pada pihak yang bersengketa dalam keadaan
seperti semula. Istilah teori penyelesaian sengketa berasal dari terjemahan
bahasa Inggris, yaitu dispute settlement theory, bahasa Belandanya, yaitu
theorie van de beslecthing van geschillen, sedangkan dalam bahasa
Jerman disebut theorie der streitbeilegung. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z.
Rubin mengemukakan pengertian sengketa, sebagai berikut.
“Persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of
interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang
bersengketa tidak dicapai secara simultan (secara serentak) “286
Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, mengartikan sengketa sebagai
keadaan dimana sengketa tersebut dinyatakan di muka atau dengan
melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya mereka mengemukakan istilah pra
konflik dan konflik. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak
puas seseorang. Konflik itu sendiri adalah keadaan di mana para pihak
menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas
tersebut”.287
Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani mengemukakan bahwa
sengketa adalah :
285
Fuadi menjelaskan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah: a) adanya suatu
perbuatan, b) pcrbuatan tersebut melawan hukum; c) adanya kesalahan dari pihak pelaku: d)
adanya kerugian bagi korban; dan e) adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan
kerugian.
Lihat Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya
Bakti, Jakarta, 2005, hlm. 10-11 286
Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 9-
10. 287
Valerine J.L. Kriekhoff, Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum), dalam Antropologi
Hukum : Sebuah Bunga Rampai oleh T.O. Ihromi, Yayasan Obor, Jakarta, 2001, hlm. 225.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
140
“Pertentangan, perselisihan atau percekcokan yang terjadi antara yang
satu dengan pihak yang lainnya dan / atau antara pihak yang satu dengan
berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik berupa
uang maupun benda”.
Berdasarkan rumusan diatas, Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani
merumuskan teori penyelesaian sengketa, yaitu teori yang mengkaji dan
menganalisis tentang :
“Kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul
dalam masyarakat, faktor terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi
yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut”.288
Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara
penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:289
1) Lumpingit (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan
perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia
mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau
isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan
hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan
merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti
kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan
keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau
sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa
kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari
sisi materi maupun pisikologis.
2) Avoidance (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan,
memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak
yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan
hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa
288
Salim H.S. & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 137 289
Laura Nader & Harry F. Todd Jr, The Disputing Process Law in Ten Societies, Columbia
Univerity Press, New York, 1978, hlm. 9-11
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
141
bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang
menimbulkan keluhan dielakkan saja.
Berbeda dengan pemecahan pertama (lumping it), dimana
hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang
dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (avoidance),
yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk
penyelesaian pertama hubungan pihak yang besengketa tetap
diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belak
pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau
untuk keseluruhan.
3) Coercion (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan
kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat
memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada
umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaiaan secara damai.
4) Negotiation (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan
merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang
dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa
adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah
pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat
aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik
tolak dari aturan-aturan yang ada.
5) Mediation (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah
pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan.
Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang
bersengketa, atau ditunjukan oleh pihak yang berwenang untuk itu.
Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena
ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah
pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang
mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam
masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
142
sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai
hakim.
6) Arbitration (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa
sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator
dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima
keputusan dari arbitrator tersebut.
7) Adjudication (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai
wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari
keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga
berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya
pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.
Ketujuh cara ini dapat dibagi menjadi tiga cara penyelesaian
sengketa yaitu tradisonal, alternative disputeresolution (ADR) dan
pengadilan. Cara tradisional adalah lumping it (membiarkan saja),
avoidance (mengelak) dan coercion (paksaan). Ketiga cara tersebut
tidak dapat ditemukan dalam perundang-undangan. Yang termasuk
dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan ADR adalah
perundingan (negotiation), mediasi dan arbitrase. Ketiga cara ini
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, sedangkan
penyelesaian sengketa di pengadilan dikenal dengan hukum acara.
Dalam hukum perdata diperkenalkan dua jalur penyelesaian
sengketa: a) jalur pengadilan; dan b) jalur musyawarah. Akan tetapi,
dalam ilmu hukum juga diperkenalkan alternatif lain, yaitu jalur
arbitrase (perwasitan).290
Jalur pengadilan disebut juga dengan jalur
litigasi, danjalur selain jalur pengadilan disebutjalur nonlitigasi. Jalur
nonlitigasi dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrasi291
290
Richard Burton Simatupang. Aspek Hukum dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 41 291
Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar,
Fikahati Aneska dan BANI, Jakarta, 2002, hlm. 2l-27
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
143
Mengenai penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi),
Robert Cooter menyatakan sebagai berikut.292
“ A legal dispute arises when someone claims to have been
illegally harmed at the hands of another. It is possible that
the victim and the injurer can resolve their dispute
themselves, but sometimes they cannot. The person who
feels injured may have a cause of action, that is, a valid
legal claim, against another person or organization. To
assert that action, he files a complaint and is, therefore,
referred to as the plaintiff. The complaint must state what
has happened, why the plaintiff feels that he has been
injured, what area of law is involved, what statute or other
law is relevant, and what relief he wishes the court to give
him. The complaint and the management of the subsequent
aspects of the dispute are complicated matters; typically,
private citizens retain the services of a lawyer, who usually
has far more experience in these matters than does the
citizen, to help them in all this.”
Penyelesaian perselisihan kontrak syari’ah telah
diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, di dalam undang-undang ini
ditetapkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a)
perkawinan; b) waris; e) wasiat; d) hibah; e) wakaf; t) zakat; g)
infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syri’ah.
Pembahasan pada rumusan masalah pertama akan
mengaplikasikan teori penyelesaian sengketa yang mengarah
kepada hukum manakah yang digunakan dan dalam situasi apa
hukum tersebut digunakan oleh hakim yang memeriksa dan
memutus perkara kepailitan di bidang ekonomi syaria’ah. Teori
aanknopingspunten (pertautan/titik-titik pertalian hukum)
adalah menyangkut hal-hal dan keadaan-keadaan yang
292
Roger Cooter & Thomas Ulen, Law and Economics ( 6th edition), Addison-Wesley, Boston,
2012, hlm. 62
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
144
menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum. Secara umum,
pertautan hukum dibedakan menjadi dua: pertautan hukum
yang bersifat primer dan pertautan hukum yang bersifat
sekunder.293
Pertautan primer merupakan alat-alat utama guna
pelaksanaan hukum, terutama hakim-untuk mengetahui apakah
(kedudukan/posisi) suatu perselisihan hukum merupakan
masalah hukum antar tata hukum sehingga melahirkan
hubungan hukum antar tata hukum. Pertautan primer
mencakup: a) para pihak (partijen) atau subyek hukum; b)
tanah; c) pilihan hukum (rechtskeuze); d) hakim sebagai titik-
pertalian mengenai hukum acara.
Titik pertautan sekunder (secunadaire aanknopingspunten)
mencakup: a) maksud para pihak (bedoiing van partiej); b)
lingkungan dan suasana tempat dilakukannya perjanjian; c)
kedudukan pihak-pihak yang melakukan perjanjian; d) masuk
dalam suasana hukum pihak yang lain (zich begeven in de
rechttssfeer van den ander); dan e) tanah pada perjanjian
obligatoir (niet zakelijke overeenkomten) merupakan salah satu
pertautan hukum sekunder.
Gautama dengan mengutip pendapat Klein menyajikan tiga
bentuk pernyataan yang menunjukan berlakunya hukum bagi
pihak yang melakukan perbuatan hukum yang berupa: a)
pernyataan berlaku secara langsung (rechtstreekse
toepasselijkverklaring), b) pernyataan berlaku secara tidak
langsung (middelijke toepasselzjkverklaring), dan e) peraturan-
peraturan khusus untuk masalah-masalah hukum
antargolongan.294
293
Sudargo Gautama, Hukum Antargolongan: Suatu Pengantar (Cetakan Ke-6) , PT Ichtiar Baru-
Van Hoeve, Jakarta, 1983, hlm. 47. 294
ibid
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
145
4. Teori Kewenangan.
Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu
authority of theory, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu
theorie van het gezag, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu theorie
der autorität. Menurut H.D Stoud wewenang adalah pengertian yang
berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan
sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan
penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum
publik di dalam hubungan hukum publik.295
Dalam kepustakaan hukum
administrasi Belanda, soal wewenang selalu menjadi bagian penting dan
bagian awal dari hukum administrasi karena obyek administrasi adalah
wewenang pemerintahan ( bestuursbevoegdheid ). Dalam konsep hukum
publik, wewenang merupakan suatu suatu konsep inti dalam hukum tata
negara dan hukum administrasi.296
Dalam hukum tata negara, wewenang
(bevogheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechsmacht). Jadi
dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.297
Hench van Maarseveen menyebutkan bahwa sebagai suatu konsep
hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen,
yaitu :
1) Pengaruh;
2) Dasar hukum; dan
3) Konformitas hukum.298
Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksud
untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. komponen dasar hukum
ialah bahwa wewenang itu harus selalu dapat ditunjuk dasar hukumnya 295
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 71. 296 F.A.M. Stroink-J.G. Steenbeek, Inlelding in Het Staats Administratie Recht, Samson, 1983,
hlm. 26 dalam Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Jurnal Yuridika, hlm. 1 297 Henc van Maarseveen, Bevoegdheid, dimuat dalam P.W. C. Akkermans et al., Algemene
Begrippen van Staatsrecht, Tjeenk Willink, 1985, hlm. 47 dalam Philipus M. Hadjon, ibid. 298
Henc van Maarseveen, Bevoegdheid, dimuat dalam P.W. C. Akkermans et al., Algemene
Begrippen van Staatsrecht, Tjeenk Willink, 1985, hlm. 49 dalam Philipus M. Hadjon,
“Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)”, Pro Justisia Tahun XVI Nomor 1
Januari 1998, hlm. 94.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
146
dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar
wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar
khusus (untuk jenis wewenang tertentu).
Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan
yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu:
1) Adanya aturan-aturan hukum; dan
2) Sifat hubungan hukum.
Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang
melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan
pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat
hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut
atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan
hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.
Ateng Syarifudin menyajikan pengertian wewenang, mengemukakan
bahwa :
“Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita
harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dengan
wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang
disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan
yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya
mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.
Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang ( rechtsbe
voegdheden). Wewenang merupakan ruang lingkup tindakan hukum
publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi
wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi
wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan
wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan”.299
Ateng Syafrudin, tidak hanya menyajikan konsep kewenangan, tetapi
juga konsep tentang wewenang. Unsur-unsur yang tercantum dalam
kewenangan, meliputi :
299
Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan
Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000,
hlm. 22.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
147
1) Adanya kekuasaan formal; dan
2) Kekuaasaan diberikan oleh undang-undang.
Indroharto menyajikan pengertian wewenang. Wewenang dalam arti
yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat
hukum”.300
Sementara itu, pengertian kewenangan ditemukan dalam Black Law
Dictionary. Kewenangan atau authority adalah :
“Right to exercise power; to implement and enforce laws; to exact
obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often
synonymous with power”.301
Konstruksi tersebut diatas, kewenangan tidaknya diartikan sebagai hak
untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan:
1) Untuk menerapkan dan menegakkan hukum;
2) Ketaatan yang pasti;
3) Perintah;
4) Memutuskan;
5) Pengawasan;
6) Yurisdiksi;
7) Kekuasaan
Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani mendefiniskan teori
kewenangan (authority theory) sebagai teori yang mengkaji dan
menganalisis tentang :
“ Kekuasaan organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya,
baik dalam lapangan hukum publik maupun lapangan hukum privat
“. Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan meliputi
kekuasaan, organ pemerintah dan sifat hubungan hukumnya.
Kewenangan dapat dilihat dibedakan menurut sumber,
kepentingannya, teritoria, ruang lingkupnya dan menurut urusan
300
Indroharto dalam Salim HS dan Erlies Septiana, Op.Cit, hlm. 185 301
Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Op.Cit. hlm 121.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
148
pemerintah. Kewenangan menurut sumbernya dibedakan menjadi dua
macam, yaitu wewenang personal dan wewenang official. Wewenang
personal yaitu wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman,
nilai, atau norma dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan
wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari
wewenang yang berada diatasnya.
Max Weber membagi kewenangan menjadi empat macam, yang
meliput:
1) Wewenang kharismatis, traditional dan rasional (legal);
2) Wewenang resmi dan tidak resmi;
3) Wewenang pribadi dan teritorial; dan
4) Wewenang terbatas dan menyeluruh.
Wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan
pada kharisma yang merupakan suatu kemampuan khusus yang
melekat pada diri seseorang, kemampuan mana yang diyakini sebagai
pembawaan seorang sejak lahir. Wewenang tradisional merupakan
wewenang yang dapat dipunyai oleh seseorang atau kelompok orang.
Ciri-ciri wewenang tradisional, meliputi:
1) Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa
yang mempunyai wewenang, serta orang-orang lainnya dalam
masyarakat;
2) Adanya wewenang yang lebih tinggi daripada kedudukan seorang
diri hadir secara pribadi;
3) Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan
tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas.
Wewenang rasional atau legal, yaitu wewenang yang disandarkan
pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, sistem hukum
mana dipahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta
ditaati oleh masyarakat, dan bahkan telah diperkuat oleh negara.
Wewenang tidak resmi merupakan hubungan-hubungan yang
timbul antar pribadi yang sifatnya situasional, dan sifatnya sangat
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
149
ditentukan pihak-pihak yang saling berhubungan tadi. Wewenang
resmi sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan dan rasional. Biasanya
wewenang ini dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang
memerlukan aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap.
Wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi, dan/atau
kharisma. Wewenang teritorial merupakan wewenang dilihat dari
wilayah tempat tinggal. Wewenang terbatas adalah wewenang yang
sifatnya terbatas, dalam arti tidak mencakup semua sektor atau bidang
kehidupan, akan tetapi hanya terbatas pada salah satu sektor atau
bidang saja. Misalnya, seorang jaksa di Indonesia mempunyai
wewenang atas nama negara menuntut seorang warga negara yang
melakukan tindak pidana, akan tetapi jaksa tersebut tidak berwenang
untuk mengadilinya. Wewenang menyeluruh merupakan wewenang
yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Sebagai
contoh adalah, bahwa setiap negara mempunyai wewenang yang
menyeluruh atau mutlak untuk mempertahankan kedaulatan
wilayahnya.
Fokus Penulis dalam menerapkan teori kewenangan adalah untuk
mengkaji sumber kewenangan dari pengadilan agama dan pengadilan
niaga dalam memutus perkara kepailitan di bidang ekonomi syari’ah
dengan mendasarkan pada pendapat Philipus M. Hadjon. Philipus M.
Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara utama,
yaitu 1) atribusi dan 2) delegasi dan kadang-kadang juga mandat.302
1) Atribusi dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh
wewenang pemerintahan.303
Atribusi merupakan wewenang untuk
membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada
undang-undang dalam arti materiil.304
Sebagaimana telah
302 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Jurnal Yuridika, hlm. 2 303 Van Wijk/Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratitief Recht, vijfde druk, Vuga, 1984,
hlm. 51 dalam Philipus M. Hadjon, ibid. 304
Rapport v.d. Commissie inzake algene bepalingen van administratief recht, Algemene
Bepalingen van Administratie Recht, Samson, 1984, hlm. 11 dalam Philipus M. Hadjon, ibid.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
150
disampaikan bahwa sebagai suatu cara normal untuk memperoleh
wewenang pemerintahan, kewenangan yang didapat melalui
atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena
kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-
undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi
berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan
itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintahan yang bersangkutan.
Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan
pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ
tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2) Delegasi, dalam artikel 10:3 Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)
diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat besluit)
oleh pejabat pemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) kepada
pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak
lain tersebut. Yang memberi/melimpahkan wewenang disebut
delegans dan yang menerima disebut delegataris.305
Dengan kata
penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari
yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima
(delegataris).
Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara
lain:306
(1) Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi
menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
(2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, artinya delegasi hanya dimungkingkan kalau ada
ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan
(3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan
hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
305 J. B. J. M. Ten Berge., Besturen Door de Overheid, Netherlands Algemeen Bertuursrecht 1,
Tweede druk, Tjeenk Willink, 1985, hlm. 89 dalam Philipus M. Hadjon, ibid. hlm. 3 306
ibid. hlm. 3
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
151
(4) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi
berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan
wewenang tersebut;
(5) Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegasi memberikan
instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.307
Seperti telah diuraikan di atas, delegasi tidak dilakukan kepada
bawahan. Dalam kepustakaan digunakan istilah dekonsentrasi,
yaitu kemungkinan terjadinya pemberian wewenang dalam
hubungan kepada bawahan. Dekonsentrasi diartikan sebagai
atribusi wewenang kepada para pegawai (bawahan). Tujuan
diadakannya dekonsentrasi ialah :
a) Adanya sejumlah besar permohonan keputusan dan
dibutuhkannya keahlian khusus dalam pembuatan keputusan;
b) Kebutuhan akan penegakan hukum dan pengawasan;
c) Kebutuhan koordinasi.
3) Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan.
Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan
untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang
memberi mandat. Tanggung jawab tidak pindah ke mandataris,
melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat,
hal ini dapat dilihat dari kata a.n. (atas nama). Dengan demikian,
semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan
yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si
pemberi mandat.
Berdasarkan landasan teori yang Penulis uraikan sebagaimana
tersebut diatas, melalui penelitian disertasi ini Penulis hendak merancang
Teori Pembangunan Hukum Ekonomi Islam dengan bertitik tumpu pada
penguatan fungsi institusi peradilan agama sebagai lembaga penyelesaian
sengketa yang adil dan efektif
307
Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)”, Pro Justisia
Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, hlm. 94.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
152
C. PENELITIAN YANG RELEVAN
Penulis telah melakukan penelusuran untuk mendapatkan penelitian-
penelitian guna menghindarkan Penulis dari plagiasi dan menunjukkan
kebaruan (novelty) penelitan. Penelitian Disertasi yang menurut Penulis masih
memiliki sedikit relevansi dengan penelitian Penulis antara lain:
No. Nama dan Instansi
Perguruan Tinggi
Judul dan Ruang Lingkup Penelitian Perbedaan dengan
Penelitian Penulis
1 Nasrudin
(Universitas Islam
Negeri Alauddin
Makassar)
Disertasi, 2014, Peradilan Agama dan
Sengketa Ekonomi Syariah.
Ruang lingkup :
Disertasi ini membahas tentang Peradilan
Agama dalam kaitannya dengan Sengketa
Ekonomi Syariah.
Nasrudin dalam penelitiannya mengkaji
tentang hakikat peradilan agama dan
ekonomi syariah, peluang dan hambatan
yang muncul dalam menyelesaikan
sengketa ekonomi syariah di Indonesia,
termasuk ketika dikaitkan dengan posisi
dan fungsi hakim pengadilan agama dan
korelasi peradilan agama dengan sengketa
ekonomi syariah.
Penelitian Nasrudin
membahas mengenai
eksistensi Peradilan
Agama dan
kewenangannya dalam
menyelesaikan sengketa
ekonomi syariah serta
peluang dan hambatan
yang muncul dalam
melaksanakan
kewenangannya tersebut.
Penelitian Penulis tidak
hanya mengkaji eksistensi
Peradilan Agama dan
kewenangannya dalam
menyelesaikan sengketa
ekonomi syariah, akan
tetapi juga mengkaji
tentang kewenangan dalam
memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara
kepailitan di bidang
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
153
ekonomi syari’ah.
2. Asep Iwan Iriawan
(Universitas
Padjajaran, Bandung)
Disertasi, 2010, Kajian Atas Kewenangan
Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian
Sengketa Bisnis Dihubungkan dengan Asas
Kepastian Hukum sebagai Upaya
Pengembangan Sistem Peradilan
Indonesia.
Ruang lingkup :
Tema utama Penelitian ini adalah objek
pengadilan niaga dikaitkan dengan asas
kepastian hukum.
Asep Iwan Iriawan berpendapat dalam
disertasinya bahwa Undang-Undang
Kepailitan yang mencantumkan kata-kata
‘perniagaan lainnya’ hal ini bertentangan
dengan asas hukum yang berlaku, dimana
dalam membuat undang-undang harus
tegas, rinci, dan absolut. Undang-undang
Kepailitan menimbulkan adanya
ketidakpastian.
Demikian pula, Asep Iwan Iriawan
berpendapat bahwa sengketa bisnis yang
diajukan ke Pengadilan Niaga pun berbagai
macam kasus, akan tetapi kewenangan
Pengadilan Niaga ini tidak jelas dan tegas
disebutkan dalam Undang-Undang
Kepailitan.
Asep Iwan Iriawan pun berpendapat bahwa
sebaiknya kedudukan dan kewenangan
Pengadilan Niaga dilakukan dalam “kamar
Penelitian yang dilakukan
oleh Asep Iwan Iriawan
mengkaji tentang obyek
sengketa, atau kompetensi
absolut Pengadilan Niaga
yang tidak jelas definisi
dan ruang lingkupnya
sehingga melanggar asas
kepastian hukum.
Penelitian penulis,
meskipun sama-sama
mengkaji kompeteni
absolut dan kepastian
hukum, lebih berfoku
kepada penyeleaian
perkara-perkara kepailitan
di bidang ekonomi syariah
dengan membandingkan
kewenangannya dengan
Peradilan Agama,
sehingga luarannya pun
berbeda.
Penulis memiliki luaran
penelitian (novelty) yaitu
dibentuknya Pengadilan
Niaga Syariah di bawah
Peradilan Agama.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
154
khusus” secara terspesialisasi dalam
Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan guna
mencapai kepastian hukum dalam
pengembangan sistem peradilan untuk
mewujudkan tujuan negara kesejahteraan
yang diimplementasikan dengan landasan
hukum yang jelas, tegas, dan rinci sesuai
dengan asas peradilan sederhana, cepat,
dan biaya ringan.
3. Gunardi
(Univeritas
Tarumanegara,
Jakarta)
Disertasi, 2016, Penalaran Hukum Hakim
Pengadilan Niaga Menurut Sistem
Peradilan Indonesia
Ruang Lingkup :
Penelitian Gunardi berfokus pola penalaran
hakim pengadilan niaga. Gunardi
menyimpulkan tiga asas dan prinsip hukum
yang diterapkan hakim dalam
pertimbangan hakim.
Pertama, pada tingkat pertama di
Pengadilan Niaga, asas dan prinsip hukum
yang diterapkan hakim tentang persyaratan
utang, putusan pailit tidak dapat dijatuhkan
terhadap debitor yang masih solven,
putusan pailit harus disetujui oleh para
kreditor mayoritas, dan keadaan diam.
Selain itu dipakai juga asas pengakuan hak
separatis kreditor pemegang hak jaminan,
proses pailit tidak panjang, dan proses
pailit terbuka untuk umum.
Relevansi penelitian
Gunardi dengan penelitian
Penulis adalah sama-sama
mengkaji pola penalaran
hakim pengadilan niaga
yang tercerin dalam
pertimbangan putusan-
putusan.
Perbedaannya adalah,
Penulis lebih berfokus
kepada putusan-putusan
perkara kepailitan di
bidang ekonomi syari’ah.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
155
Kedua, pada tingkat kasasi, hakim lebih
mempertimbangkan asas keseimbangan,
keadilan, restrukturisasi utang bagi debitor
prospektif, paritas creditorium, pari passu
prorate parte, dan structural creditors.
Ketiga, di tingkat PK, hakim agung banyak
mempertimbangkan prinsip kelangsungan
usaha, integrasi, mendorong investasi dan
bisnis, memberikan manfaat dan
perlindungan, dan pengurus perusahaan
pailit harus bertanggung jawab secara
pribadi. Prinsip lain yang dipakai adalah
perbuatan merugikan harta pailit adalah
tindak pidana, debt collection, debt
pooling, debt forgiveness, serta asas
universal dan teritorial.
4. Asasriwarni
(Universitas Islam
Negeri Sunan
Kalijaga, Yogyakarta)
Disertasi, 2008, Studi Tentang Putusan-
Putusan Pengadilan Agama sebagai Produk
Pemikiran Hukum Islam (Kasus Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun
1989-1997)
Ruang Lingkup :
Penelitian Aswinarni berfokus pada
karakteristik putusan-putusan Pengadilan
Agama dan putusan-putusan Pengadilan
Agama sebagai pembaruan hukum Islam.
Aswinarni berpendapat bahwa :
a. Ada 3 (tiga) karakteristik putusan
pengadilan agama oleh hakim-
Relevansi dengan
penelitian Penulis adalah
sama-sama menggunakan
pendekatan historis,
mengkaji eksistensi
pengadilan agama dan
meneliti potensi
pembaruan hukum Islam
melalui putusan-putusan
pengadilan.
Perbedaannya adalah
Penulis mengkaji filosofi
pembentukan pengadilan
agama dan pengadilan
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
156
hakim pengadilan agama di wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Padang
tahun 1989-1997 yaitu berperan 1)
sebagai corong undang-undang, 2)
berpaling pada ketentuan fiqih dan
3) aspiratif terhadap urf.
b. Putusan pengadilan agama oleh
hakim-hakim pengadilan agama di
wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Padang sebagian telah beranjak dari
imam mazhab-mazhab yang ada;
c. Putusan pengadilan agama oleh
hakim-hakim pengadilan agama di
wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Padang sebagian memberikan
pembaharuan terhadap hukum
Islam.
niaga dan eksistensinya,
putusan-putusan perkara
kepailitan di bidang
ekonomi syariah serta
implikasinya pada
pembaruan hukum Islam
di Indonesia.
5. Siti Anisah
( Universitas
Indonesia )
Disertasi, 2008, Perlindungan Kepentingan
Kreditor dan Debitor dalam Hukum
Kepailitan di Indonesia.
Ruang Lingkup :
Penelitian Siti Anisah berfokus pada
perkembangan perlindungan terhadap
kepentingan kreditor dan debitor dalam
hukum kepailitan di Indonesia, sikap
pengadilan dalam usaha melindungi
kepentingan kreditor, debitor, dan
stakeholder, serta persamaan dan
perbedaan antara hukum kepailitan Barat
Relevansinya dengan
penelitian Penulis adalah
sama-sama mengkaji
kepailitan dalam perspektif
Islam.
Perbedaannya adalah pada
outputnya, Penulis
berfokus pada
pembentukan pengadilan
niaga syari’ah sedangkan
penelitian Siti Anisa
berfokus pada
perlindungan hukum
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
157
dengan hukum kepailitan Islam yang
melindungi kepentingan kreditor dan
debitor.
Siti Anisah menyimpulkan bahwa :
1. Perlindungan terhadap kepentingan
kreditor semakin bertambah tegas
dalam Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004;
2. Implementasi Undang-Undang
Kepailitan lebih berpihak terhadap
debitor. Buktinya adalah jumlah
debitor yang dinyatakan pailit
kurang dari 50% dari jumlah
permohonan pernyataan pailit yang
diajukan ke Pengadilan Niaga.
3. Persamaan antara hukum kepailitan
Islam dan hukum kepailitan Barat
terdapat sedikitnya di dalam tujuh
hal, yaitu mengenai pengertian dasar
dalam pailit, para pihak yang berhak
mengajukan pailit, persyaratan
pailit, pernyataan pailit diputuskan
oleh Pengadilan, ketidakcakapan
debitor setelah adanya putusan
pailit, perdamaian, dan pembebasan
utang.
Salah satu perbedaannya antara lain
adalah dalam hukum kepailitan Islam
debitor dapat saja secara gradual
diberikan status dalam keadaan tidak
kepada kepentingan
debitor, kreditor.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
158
mampu membayar utangnya (mu’sir).
Status ini dapat berubah menjadi pailit
(muflis) apabila ternyata utang debitor
melebihi jumlah harta yang
dimilikinya.
6.
Aden Rosadi.
(Universitas Islam
Negeri Sunan Gunung
Jati)
Disertasi, 2012, Nazhariyyat al-Tanzhimi
al- Qadhai ( Teori dan Sistem
Pembentukan Hukum Peradilan Agama)
dan Transformasinya dalam Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia.
Ruang Lingkup :
Penelitian Aden Rosadi berfokus pada
perubahan Undang-Undang yang mengatur
tentang Peradilan Agama di Indonesia.
Aden Rosadi berpendapat bahwa :
1. Perubahan nazhariyyat al-tanzhīmi al-
qadhāī dilatarbelakangi oleh faktor
filosofis, yuridis, sosiologis, dan
politis; Perubahan undang-undang
tentang Peradilan Agama pada tahun
2009 disebabkan oleh perubahan iklim
politik secara nasional melalui
reformasi yang bergulir sejak tahun
1998.
2. Implementasi nazhāriyyat al-tanzhīmi
al-qadhāī dalam Undang-Undang
No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Agama diarahkan pada aspek substansi,
Relevansinya dengan
penelitian Penulis adalah
sama-sama meneliti
dengan pendekatan historis
pembentukan Peradilan
Agama serta perubahan-
perubahannya.
Perbedaannya, penelitian
Penulis hanya terfokus
pada kewenangan
pengadilan agama dalam
memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa
ekonomi syarah, tidak
sampai pada ranah
implementasi.
Kedua, Penulis juga
menkaji eksistensi
Pengadilan Niaga.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
159
struktur, dan kultur hukum Peradilan
Agama;
3. Undang-Undang No.50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama memiliki
keserasian dan keselarasan, baik
vertikal (undang-undang yang lebih
tinggi) maupun horisontal (undang-
undang yang sejajar).
7.
Wakhidun
Abdurrakhman
( Universitas Sebelas
Maret, Surakarta )
Disertasi, 2018, Politik Hukum Dalam
Pembinaan Peradilan Agama di Indonesia.
Ruang Lingkup Penelitian :
Penelitian Wakhidun Abdurrakhman
berfokus kepada politik hukum
pembinanaan Peradilan Agama di
Indonesia.
Hasil Penelitian :
1) Selama masa pemerintahan orde lama,
keberadaan Peradilan Agama tidak jauh
berubah sebagaimana di masa Pra
Kemerdekaan, sebab ternyata politik
kaum kolonialisme yang tidak
mensejajarkan Peradilan Agama
dengan Peradilan Umum masih tetap
diberlakukan.
2) Politik hukum dalam membina
Peradilan Agama di Indonesia : terjadi
pergeseran kekuasan dari rezim orde
baru ke orde reformasi membawa
Relevansi dengan
penelitian Penulis adalah
sama sama terdapat kajian
tentang politik hukum dan
ada gagasan tentang
Pengadilan Niaga Syariah.
Perbedaan :
1) Penelitian Wakhidun
Abdurrakhman
seluruhnya adalah
tentang politik hukum
pembinaan Peradilan
Agama, sedangkan
dalam penelitian
Penulis, politik hukum
pembentukan peradilan
agama hanya dijadikan
sub bab pembahasan
saja dan
diperbandingkan
dengan pengadilan
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
160
berbagai perubahan dalam ranah sosial,
politik, dan hukum, serta lahirnya
peradilan khusus di daerah Propinsi
Aceh Darussalam.
3) Politik hukum dalam pembinaan
Peradilan Agama yaitu perlu diperkuat
dan dipercepat lahirnya Peradilan
Ekonomi Syariah (Niaga Syariah)
karena keberadaannya sangat
dibutuhkan dalam menyelesaikan
adanya sengketa ekonomi syariah.
niaga.
2) Pengadilan Ekonomi
Syariah yang digagas
oleh Wakhidun
Abdurrakhman
memiliki kompetensi
memeriksa seluruh
perkara ekonomi
syariah, sedangkan
Pengadilan Niaga
Syariah memiliki
kewenangan
memeriksa kepailitan
di bidang ekonomi
syariah saja.
Tabel 3. Penelitian yang relevan.
Berdasarkan tabel 3 sebagaimana tersebut diatas, maka penelitian Penulis
belum ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya karena tema juga berbeda. Ada pun
tema atau rumusan yang Penulis angkat dalam disertasi ini antara lain 1)
implikasi dari diperiksa dan diadilinya perkara kepailitan di bidang ekonomi
syariah oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum 2)
dasar pembenaran pemeriksaan perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah oleh
Pengadilan Niaga pasca berlakunya UU No. 3/2006 jo. UU No. 50/2009 yang
telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili
dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah dan 3) kebijakan hukum
yang ideal terkait kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili serta
menyelesaikan perkara kepailitan di bidang ekonomi Syariah antara Pengadilan
Niaga dan Pengadilan Agama (ius constituendum).
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
161
Demikian pula dengan kebaruan penelitian Penulis sangat berbeda dengan
penelitian-penelitian sebelimnya sebagaimana tersebut di atas. Penulis
mengemukakan model penyelesaian perkara kepailitan di bidang ekonomi
syari’ah yaitu dengan pembentukan pengadilan niaga syari’ah. Demikian pula
Penulis merancang teori pembangunan hukum ekonomi Islam dengan bertitik
tumpu pada penguatan fungsi peradilan agama.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
162
D. KERANGKA BERPIKIR
UUD RI 1945
Ps. 24 ayat (2) UUD RI 1945 jo. UU
No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman
Peradilan Militer
Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah
Konstitusi
Mahkamah
Agung
Peradilan Umum Peradilan Agama
Teori Lingkaran
Konsentris UU No. 49 /2009
tentang Peradilan
Umum
UU No. 50 /2009
tentang Peradilan
Agama Teori Kepastian
Hukum
Teori Kewenangan
Hukum
Islam
(Al-
Qur’an,
Hadits\,
KHI,
KHES,
dll
Pengadilan
Negeri KUHPerdata Pengadilan
Agama Teori Penyelesaian
Sengketa ( Pertautan )
Pengadilan Niaga
UU No. 37 / 2004
tentang
Kepailitan dan PKPU
Ps. 49 UU No.
50/2009 :
Sengketa
Ekonomi Syariah
Merupakan
Kewenangan
Pengadilan
Agama
Perkara Kepailitan
yang timbul
berdasarkan akad-
akad berdasarkan
prinsip Islam
(ekonomi Syariah)
Implikasi
Novelty
Teori Sistem TOPPIKU
(Sistem Peradilan yang
Terpadu dengan
Orientasi Peradilan
pada Pembangunan
Perekonomian dengan
upaya penerapan Islam
secara Kaffah dan
berparadigma Ulul
Albab)
Pembentukan
Pengadilan Niaga
Syarah di bawah
lingkungan Peradilan
Agama
Ius Constituendum:
Pengadilan Agama
diberikan kewenangan
mengadili perkara
kepailitan di bidang
ekonomi syari’ah
Dasar Pembenaran
Kebijakan yang Ideal
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
163
Bagan 1. Kerangka Berpikir
Keterangan :
Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki
kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-
perkara kepailitan. Pengadilan Niaga yang secara kelembagaan berada di
lingkungan peradilan umum dalam menjalankan kewenangan absolutnya untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara kepailitan tidak
membedaka-bedakan antara perkara kepailitan yang timbul dari kontrak-kontrak
konvensional mau pun kontra-kontrak (akad) syariah, dengan kata lain Pengadilan
Niaga tidak mengenal pembedaan antara kontrak konvesional dengan akad
syariah. Setiap perkara kepailitan yang diajukan, selama memenuhi unsur terdapat
lebih dari dua kreditur, hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta
memenuhi asas pembuktian yang sederhana, akan diterima oleh Pengadilan Niaga
untuk selanjutnya diperiksa dan diadili, tidak perlu diperhatikan apakah perkara
kepailitan tersebut timbul dari kontrak-kontrak konvensional atau akad-akad
syariah yang kemudian dikenal dengan istilah sengketa ekonomi syariah.
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 59 “Wahai orang-
orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri
di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” Firman Allah SWT tersebut diatas
merupakan pedoman bagi orang-orang yang beragama Islam dalam
menyelesaiakan perkara-perkara yang timbul termasuk perkara ekonomi syariah.
Demikian pula, dalam hukum positif di Indonesia, sengketa ekonomi syariah
berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
164
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah
menjadi kewenangan absolut dari Pegadilan Agama di bawah lingkungan
Peradilan Agama. Artinya, setiap perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi
syariah merupakan kompetensi absolut dari pengadilan agama dan harus
diselesaikan di Pengadilan Agama dengan berlandaskan syariat Islam.
Isu hukum utama yang dalam penelitian ini adalah dasar pembenaran
kewenangan mengadili Pengadilan Niaga apabila terdapat sengketa kepailitan
yang timbul berdasarkan kepada akad-akad yang menggunakan prinsip syariah.
Sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU, maka Pengadilan Niaga di bawah
Peradilan Umum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara, akan tetapi
berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, perkara-perkara dalam ruang
lingkup kontrak syariah di bidang ekonomi menjadi kompetensi absolut
Pengadilan Agama di bawah lingkungan Peradilan Agama. Artinya, apabila sudah
dibentuk Pengadilan Agama, seharusnya semua perkara terkait ekonomi syariah,
termasuk kepailitan di bidang ekonomi syariah menjai kewenangan Pengadilan
Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan. Kewenangan memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah di bidang kepailitan oleh
pengadilan niaga tentu memberikan implikasi bagi penegakan hukum Islam di
bidang muamalah.
Teori yang Penulis gunakan adalah teori lingkaran konsentris, teori kepastian
hukum, teori kewenangan dan dilengkapi dengan teori pertautan. Teori tersebut
sangat relevan untuk mengalisis isu-isu hukum yang Penulis angkat ke dalam
disertasi mengingat pokok-pokok bahasan Penulis secara garis besar adalah
mengenai kepastian hukum dan kewenangan mengadili antara lembaga
pengadilan.
Novelty yang Penulis ajukan adalah mengajukan suatu model sistem peradilan
yang terpadu dengan orientasi peradilan pada pembangunan perekonomian
dengan upaya penerapan Islam secara kaffah dan berparadigma ulul albab (
Teori TOPPIKU ) dengan cara membentuk Pengadilan Niaga Syariah yang
berkedudukan di lingkungan Peradilan Agama yang memiliki kewenangan untuk
memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah.
commit to user
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id