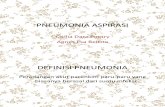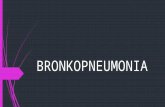Pneumonia
-
Upload
cokorda-agung-arbi-maranggi -
Category
Documents
-
view
111 -
download
13
Transcript of Pneumonia

RESPONSI KASUS
PNEUMONIA KOMUNITAS DANHIPERTENSI PADA GERIATRI
Pembimbing:dr. I G.P. Suka Aryana, Sp.PD-KGer
Mahasiswa:Cokorda Agung Arbi Maranggi (0802005163)
Roobashini Kaandan Arul Kaandan (0802005187)
DALAM RANGKA MENJALANI KEPANITERAAN KLINIK MADYADI BAGIAN ILMU PENYAKIT DALAM RSUP SANGLAHFAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
SEPTEMBER 2012

KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas
rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan responsi kasus yang berjudul
“Pneumonia Komunitas dan Hipertensi pada Geriatri” ini dengan baik dan
tepat pada waktu yang telah ditentukan. Responsi kasus ini dibuat sebagai salah
satu syarat dalam mengikuti KKM di Bagian Ilmu Penyakit Dalam RSUP
Sanglah/Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu, yaitu :
1. Prof. Dr. dr. Tjok Raka Putra, Sp.PD-KR, selaku kepala SMF Ilmu Penyakit
Dalam RSUP Sanglah.
2. dr. I GP Suka Aryana, Sp.PD-KGer, selaku pembimbing yang telah
memberikan arahan dan masukan selama pengerjaan responsi ini.
3. dr. Made Pande Dwipayana, Sp.PD, selaku Koordinator Pendidikan Dokter
Muda Fakultas Kedokteran Udayana/RSUP Sanglah.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan pengerjaan responsi
kasus ini.
Penulis menyadari bahwa response kasus ini masih jauh dari sempurna,
oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.
Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
Denpasar, September 2012
Penulis
ii

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................... i
KATA PENGANTAR ................................................................................ ii
DAFTAR ISI ............................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pneumonia ............................................................................................ 5
2.1.1 Definisi ....................................................................................... 5
2.1.2 Epidemiologi .............................................................................. 5
2.1.3 Etiologi ....................................................................................... 6
2.1.4 Patogenesis ................................................................................. 6
2.1.5 Klasifikasi ................................................................................... 8
2.1.6 Faktor Risiko .............................................................................. 10
2.1.7 Diagnosis .................................................................................... 10
2.1.8 Penatalaksanaan .......................................................................... 11
2.1.9 Komplikasi ................................................................................. 13
2.1.10 Prognosis .................................................................................. 14
2.2 Hipertensi ............................................................................................. 14
2.2.1 Definisi ....................................................................................... 14
2.2.2 Epidemiologi .............................................................................. 14
2.2.3 Klasifikasi ................................................................................... 15
2.2.4 Patogenesis ................................................................................. 19
2.2.5 Tanda dan Gejala ........................................................................ 20
2.2.6 Penatalaksanaan .......................................................................... 21
2.2.7 Pencegahan ................................................................................. 22
2.2.8 Komplikasi ................................................................................. 25
BAB III LAPORAN KASUS
3.1 Identitas Pasien .................................................................................... 27
3.2 Anamnesis ............................................................................................ 27
3.3 Riwayat Medis ..................................................................................... 30
iii

3.4 Anamnesis Sistem ................................................................................ 32
3.5 Penapisan Status Fungsional ................................................................ 34
3.6 Penapisan Kognitif ............................................................................... 37
3.7 Penapisan Depresi ................................................................................ 37
3.8 Penapisan Inkontinensia ....................................................................... 39
3.9 Penapisan Nutrisi Mini (Mini Nutritional Assessment) ....................... 40
3.10 Assesmen Lingkungan, Keamanan, Bahaya/Penyebab Jatuh ........... 42
3.11 Daftar Masalah .................................................................................. 45
3.12 Pemeriksaan Fisik .............................................................................. 46
3.13 Pemeriksaan Penunjang ..................................................................... 48
3.14 Diagnosis ........................................................................................... 50
3.15 Impairment ......................................................................................... 50
3.16 Dissability .......................................................................................... 51
3.17 Handicap ............................................................................................ 51
3.18 Penatalaksanaan ................................................................................. 51
3.19 Prognosis ........................................................................................... 51
BAB IV KESIMPULAN ............................................................................ 52
DAFTAR PUSTAKA
iv

BAB IPENDAHULUAN
Pneumonia komunitas (PK) atau community-acquired pneumonia (CAP)
masih menjadi suatu masalah kesehatan utama di seluruh dunia. Meskipun telah
dilakukan diagnosis yang tepat, pemberian terapi antibiotika yang efektif, dan
perawatan yang baik, namun PK masih memiliki angka morbiditas dan mortalitas
yang tinggi.1,2 PK merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia dan
merupakan penyebab kematian terbesar ke-6 di Amerika Serikat. Rerata jumlah
kematian akibat pneumonia meningkat dari tahun ke tahun. Di Amerika Serikat
diperkirakan terdapat 5-10 juta kasus PK setiap tahunnya dan mengakibatkan
perawatan rumah sakit sebanyak 1,1 juta serta 45.000 kematian setiap tahun.3,4
Pneumonia juga merupakan infeksi utama penyebab kematian di negara-negara
berkembang. Angka kematian pasien PK adalah 1% pada pasien rawat jalan dan
12-14% pada pasien PK yang dirawat di rumah sakit. Sekitar 10-20% pasien yang
memerlukan perawatan di rumah sakit akan berakhir di ruang intensif (ICU) dan
angka kematian diantara pasien tersebut lebih tinggi, yaitu sekitar 30-40%.5 Di
Indonesia, Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001 mencatat
kematian akibat pneumonia dan infeksi saluran nafas sebanyak 34 per 100.000
penduduk pada pria dan 28 per 100.000 penduduk pada wanita.6
Pneumonia adalah infeksi saluran napas bawah akut (ISNBA) yang
disebabkan oleh bakteri, virus, mikroplasma, jamur, berbagai senyawa kimia,
maupun partikel. Penyakit ini dapat terjadi pada semua umur, walaupun
manifestasi klinik terparah muncul pada anak, orang tua, dan penderita penyakit
kronis. Pneumonia adalah peradangan yang mengenai parenkim paru, distal dari
bronkiolus terminalis yang mencakup bronkiolus respiratorius, dan alveoli serta
menimbulkan konsolidasi jaringan paru dan gangguan pertukaran gas setempat.7
Berdasarkan tempat terjadinya, pneumonia dapat dibagi menjadi dua
kelompok utama, yaitu pneumonia komunitas (PK) atau community-acquired
pneumonia (CAP) dan pneumonia nosokomial (PN) atau hospital-acquired
pneumonia (HAP). PK merupakan pneumonia yang didapatkan di masyarakat
1

yaitu terjadinya infeksi di luar lingkungan rumah sakit yang biasanya disebabkan
oleh bakteri gram positif (Streptococcus pneumoniae). Infeksi ini terjadi dalam 48
jam setelah dirawat di rumah sakit pada pasien yang dirawat di rumah sakit
selama kurang dari 14 hari.7
PN adalah pneumonia yang terjadi lebih dari 48 jam setelah dirawat di
rumah sakit, baik di ruang rawat umum ataupun ICU tetapi tidak sedang memakai
ventilator. Dalam perkembangannya, pneumonia nosokomial ini telah
dikelompokkan menjadi pneumonia yang berhubungan dengan pemakaian
ventilator (ventilator-associated pneumonia) dan pneumonia yang didapat di pusat
perawatan kesehatan (healthcare-associated pneumonia).7
Proses patogenesis PK dikaitkan dengan tiga faktor, yaitu imunitas inang,
mikroorganisme yang menyerang pasien, dan lingkungan yang berinteraksi satu
sama lain. Dalam keadaan sehat, pada paru tidak akan terjadi pertumbuhan
mikroorganisme karena adanya mekanisme pertahanan paru. Terdapatnya bakteri
di paru merupakan akibat ketidakseimbangan antara imunitas tubuh,
mikroorganisme, serta lingkungan, sehingga mikroorganisme dapat berkembang
biak dan berakibat timbulnya sakit. Masuknya mikroorganisme ke saluran napas
dan paru dapat melalui berbagai cara, antara lain inhalasi langsung dari udara,
aspirasi dari bahan-bahan yang ada di nasofaring dan orofaring, perluasan
langsung dari tempat-tempat lain, dan penyebaran secara hematogen.7
Sampai saat ini hipertensi masih tetap menjadi masalah di seluruh dunia,
terutama pada lanjut usia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain
meningkatnya prevalensi hipertensi, banyaknya pasien hipertensi yang belum
mendapat pengobatan maupun yang sudah diobati tetapi tekanan darahnya belum
mencaai target, serta adanya penyakit penyerta dan komplikasi yang dapat
meningkatkan morbiditas dan mortalitas.8
Jumlah penduduk berusia di atas 60 tahun di Indonesia pada tahun 2010
mengalami kenaikan sebesar 400%, sehingga jumlahnya melebihi jumlah bayi di
bawah lima tahun (balita). Lanjut usia membawa konsekuensi meningkatnya
berbagai penyakit kardiovaskular, infeksi, dan stroke. Hipertensi merupakan
penyebab meningkatnya prevalensi gagal jantung dan stroke pada lanjut usia. Data
2

epidemiologis menunjukkan bahwa dengan makin meningkatnya populasi lanjut
usia, maka jumlah pasien dengan hipertensi kemungkinan besar juga akan
bertambah, dimana hipertensi sistolik sistolik maupun kombinasi hipertensi
sistolik dan diastolik sering timbul pada lebih dari separuh orang yang berusia di
atas 65 tahun. Selain itu, laju pengendalian tekanan darah yang dahulu terus
meningkat, dalam dekade terakhir tidak menunjukkan kemajuan lagi (pola kurva
mendatar), dan pengendalian tekanan darah ini hanya mencapai 34% dari seluruh
pasien hipertensi.9
Sampai saat ini, data hipertensi yang lengkap sebagian besar berasal dari
negara-negara yang sudah maju. Data dari The National Health and Nutrition
Examination Survey (NHANES) yang dilaksanakan 1999-2000 didapatkan bahwa
angka prevalensi pada populasi dewasa adalah sekitar 29-31%, yang berarti
terdapat 58-65 juta orang hipertensi di Amerika, dan terjadi peningkatan sebesar
15 juta dari data NHANES III yang dilaksanakan tahun 1988-1991.10,11 Prevalensi
hipertensi di Indonesia juga cukup tinggi. Hasil survei dari Multinational
Monitoring of Trends and Determinant in Cardiovascular Disease pada tahun
1993, prevalensi di Indonesia mencapai 16,9%. Menurut laporan dari Survei
Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995, prevalensi hipertensi pada dewasa
adalah 7,4% pada pria dan 9,1% pada wanita. Hipertensi primer atau esensial
merupakan 90% dari seluruh kasus hipertensi.9-11
Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah yang melebihi tekanan darah
normal, yaitu lebih dari atau sama dengan 140/90 mmHg.10,11 Berdasarkan
etiologinya, hipertensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer atau
esensial yang tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik dan hipertensi sekunder
yang memiliki patogenesis spesifik.10
Berdasarkan The Seventh Report of Joint National Committee on
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC-
VII) tahun 2003, klasifikasi hipertensi dapat dibagi menjadi empat, yaitu normal
(sistolik <120 mmHg dan diastolik <80 mmHg), pre-hipertensi (sistolik 120-139
mmHg dan diastolik 80-89 mmHg), hipertensi tingkat 1 (sistolik 140-159 mmHg
3

dan diastolik 90-99 mmHg), dan hipertensi tingkat 2 (sistolik ≥160 mmHg dan
diastolik ≥100 mmHg).12
Hipertensi pada lanjut usia sama seperti hipertensi pada usia lainnya.
Bahkan risiko terjadi komplikasi lebih besar. Penurunan tekanan darah
menghasilkan penurunan risiko morbiditas dan mortalitas akibat komplikasi
kardiovaskular. Pada lanjut usia, hasil pengobatan tidak hanya diukur oleh
keberhasilan penurunan tekanan darah pada morbiditas dan mortalitas
kardivaskular, tetapi juga oleh berbagai hal termasuk efek terhadap diabetes,
pencegahan demensia atau penurunan kognitif, dan pengaruhnya kepada indeks
massa tubuh (IMT).9
Pengelolaan hipertensi pada dasarnya sama pada tingkatan usia kecuali
terdapat kondisi seperti di atas. Direkomendasikan agar tekanan darah dapat
mencapai kurang dari 140/90 mmHg. Pengobatan hipertensi harus dimulai sejak
dini untuk mencegah kerusakan organ sasaran tanpa memandang usia. Pada lanjut
usia, penurunan tekanan darah harus dilakukan hati-hati dengan memperhatikan
apakah terdapat hipertensi berat yang lama. Pada hipertensi resisten diperlukan
waktu yang cukup untuk mencapai sasaran.9
Untuk mencapai sasaran pengobatan diperlukan kombinasi dua obat atau
lebih. Apabila sasaran TDS tercapai, biasanya TDD juga akan turun. Secara
umum, penggunaan obat hipertensi adalah ACE-inhibitor, angiotensin-receptor
blocker, β-blocker, calsium-channel blocker, dan diuretik mempunyai efek klinik
yang sama. Penelitian Losartan Intervention for End-point Reduction in
Hypertension), terutama pada pasien dengan hipertensi sistolik dan pembesaran
ventrikel kiri, mendapatkan hasil yang lebih baik pada pemberian Losartan
dibandingkan β-blocker, dalam hal penurunan angka kejadian stroke (25%) dan
kejadian diabetes (25%).9
4

BAB IITINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pneumonia
2.1.1 Definisi
Pneumonia adalah infeksi saluran napas bawah akut (ISNBA) yang
disebabkan oleh bakteri, virus, mikroplasma, jamur, berbagai senyawa kimia,
maupun partikel. Penyakit ini dapat terjadi pada semua umur, walaupun
manifestasi klinik terparah muncul pada anak, orang tua, dan penderita penyakit
kronis. Pneumonia adalah peradangan yang mengenai parenkim paru, distal dari
bronkiolus terminalis yang mencakup bronkiolus respiratorius, dan alveoli serta
menimbulkan konsolidasi jaringan paru dan gangguan pertukaran gas setempat.7
2.1.2 Epidemiologi
PK merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia dan
merupakan penyebab kematian terbesar ke-6 di Amerika Serikat. Rerata jumlah
kematian akibat pneumonia meningkat dari tahun ke tahun. Di Amerika Serikat
diperkirakan terdapat 5-10 juta kasus PK setiap tahunnya dan mengakibatkan
perawatan rumah sakit sebanyak 1,1 juta serta 45.000 kematian setiap tahun.3,4
Pneumonia juga merupakan infeksi utama penyebab kematian di negara-negara
berkembang. Angka kematian pasien PK adalah 1% pada pasien rawat jalan dan
12-14% pada pasien PK yang dirawat di rumah sakit. Sekitar 10-20% pasien yang
memerlukan perawatan di rumah sakit akan berakhir di ruang intensif (ICU) dan
angka kematian diantara pasien tersebut lebih tinggi, yaitu sekitar 30-40%.5 Di
Indonesia, Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001 mencatat
kematian akibat pneumonia dan infeksi saluran nafas sebanyak 34 per 100.000
penduduk pada pria dan 28 per 100.000 penduduk pada wanita.6
5

2.1.3 Etiologi
Pneumonia dapat disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme, yaitu
bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Tabel 2.1 memuat daftar mikroorganisme dan
masalah patologis yang menyebabkan pneumonia.
Tabel 2.1. Daftar mikroorganisme yang menyebabkan pneumonia2,7
Infeksi Bakteri Infeksi Atipikal Infeksi Jamur
Streptococcus pneumoniae
Haemophillus influenza
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Gram-negatif (E. Coli)
Mycoplasma pneumoniae
Legionella pneumophillia
Coxiella burnetii
Chlamydia psittaci
Aspergillus
Histoplasmosis
Candida
Nocardia
Infeksi Virus Infeksi Protozoa Penyebab Lain
Influenza
Coxsackie
Adenovirus
Sinsitial respiratori
Pneumocytis carinii
Toksoplasmosis
Amebiasis
Aspirasi
Pneumonia lipoid
Bronkiektasis
Fibrosis kistik
2.1.4 Patogenesis
Dalam keadaan sehat, pada paru tidak akan terjadi pertumbuhan
mikroorganisme, keadaan ini disebabkan oleh adanya mekanisme pertahanan
paru. Terdapatnya bakteri di paru merupakan akibat ketidakseimbangan antara
daya tahan tubuh, mikroorganisme dan lingkungan, sehingga mikroorganisme
dapat berkembang biak dan berakibat timbulnya sakit.7
Masuknya mikroorganisme ke saluran napas dan paru dapat memlalui
berbagai cara:
a. Inhalasi langsung dari udara.
b. Aspirasi dari bahan-bahan yang ada di nasofaring dan orofaring.
c. Perluasan langsung dari tempat-tempat lain.
d. Penyebaran secara hematogen.
Diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pneumonia
yaitu:
6

a. Mekanisme pertahanan paru
Paru berusaha untuk mengeluarkan berbagai mikroorganisme yang
terhirup seperti partikel debu dan bahan-bahan lainnya yang terkumpul di
dalam paru. Beberapa bentuk mekanisme ini antara lain bentuk anatomi saluran
napas, refleks batuk, sistem mukosilier, juga sistem fagositosis yang dilakukan
oleh sel-sel tertentu dengan memakan partikel-partikel yag mencapai
permukaan alveoli. Bila fungsi ini berjalan baik, maka bahan infeksi yang
bersifat infeksius dapat dikeluarkan dari saluran pernapasan, sehingga pada
orang sehat tidak akan terjadi infeksi serius. Infeksi saluran napas berulang
terjadi akibat berbagai komponen sistem pertahanan paru yang tidak bekerja
dengan baik.
b. Kolonisasi bakteri di saluran pernapasan
Di dalam saluran napas atau cukup banyak bakteri yang bersifat
komensal. Bila jumlah mereka semakin meningkat dan mencapai suatu
konsentrasi yang cukup, kuman ini kemudian masuk ke saluran napas bawah
dan paru, dan akibat kegagalan mekanisme pembersihan saluran napas,
keadaan ini bermanifestasi sebagai penyakit. Mikroorganisme yang tidak
menempel pada permukaan mukosa saluran napas akan ikut dengan sekresi
saluran napas dan terbawa bersama mekanisme pembersihan, sehingga tidak
terjadi kolonisasi.
c. Pembersihan saluran napas terhadap bahan infeksius
Saluran napas bawah dan paru berulangkali dimasuki oleh berbagai
mikroorganisme dari saluran napas atas, akan tetapi tidak menimbulkan sakit,
ini menunjukkan adanya suatu mekanisme pertahanan paru yang efisien
sehingga dapat menyapu bersih mikroorganisme sebelum mereka
bermultiplikasi dan menimbulkan penyakit. Pertahanan paru terhadap bahan-
bahan berbahaya dan infeksius berupa refleks batuk, penyempitan saluran
napas, juga dibantu oleh respon imunitas humoral.
7

2.1.5 Klasifikasi
Berdasarkan tempat terjadinya, pneumonia dapat dibagi menjadi dua
kelompok utama, yaitu:
a. Pneumonia komunitas (PK) atau community-acquired pneumonia (CAP)
PK merupakan pneumonia yang didapatkan di masyarakat yaitu
terjadinya infeksi di luar lingkungan rumah sakit. Biasanya disebabkan oleh
bakteri gram positif (Streptococcus pneumoniae). Infeksi ini insidensinya
meningkat pada:
- Kelompok yang mengidap penyakit kronis
- Kelompok yang menderita defek imunoglobulin
- Kelompok dengan fungsi limpa berkurang atau hilang
Infeksi ini terjadi dalam 48 jam setelah dirawat di rumah sakit pada
pasien yang dirawat di rumah sakit selama kurang dari 14 hari.7
b. Pneumonia nosokomial (PN) atau hospital-acquired pneumonia (HAP)
PN adalah pneumonia yayang terjadi lebih dari 48 jam setelah dirawat
di rumah sakit, baik di ruang rawat umum ataupun ICU tetapi tidak sedang
memakai ventilator. Hampir 1% dari penderita yang dirawat di rumah sakit
mendapatkan pneumonia selama dalam perawatannya. Demikian pula halnya
dengan penderita yang dirawat di ICU, lebih dari 60% akan menderita
pneumonia.7
Dalam perkembangannya, PN ini dikelompokkan menjadi pneumonia
yang berhubungan dengan pemakaian ventilator (ventilator-associated
pneumonia) dan pneumonia yang didapat di pusat perawatan kesehatan
(healthcare-associated pneumonia).2,7
Penilaian tingkat keparahan penyakit perlu dilakukan untuk menentukan
tempat perawatan pasien CAP dengan tepat (rumah, bangsal, atau ICU), serta
untuk menentukan terapi empirik antibiotika berdasarkan tempat perawatan atau
tingkat keparahan penyakitnya. Therapeutic Guidelines: Antibiotic (Guidelines)
menganjurkan penggunaan Pneumonia Severity Index (PSI) (Tabel 1) untuk
mengarahkan tempat perawatan pasien dan pemilihan antibiotika.13
8

Table 2.2. Kalkulasi Pneumonia Severity Index (PSI)14
Karakteristik Poin
Faktor demografi
Laki-laki
Perempuan
Rumah perawatan
Penyakit penyerta
Penyakit neoplastik
Penyakit liver
Gagal jantung kongestif
Penyakit serebrovaskular
Penyakit ginjal kronik
Pemeriksaan fisik
Perubahan metal status akut
Lajun pernapasan ≥ 30/menit
Tekanan darah sistolik < 90 mmHg
Temperatur < 35 atau ≥ 40°C
Nadi ≥ 125/menit
Pemeriksaan laboratorium dan radiografi
pH arterial < 7,35
BUN ≥ 30 mg/dl (11 mmol/l)
Natrium < 130 mmol/l
Glukosa ≥ 250 mg/dl (14 mmol/l)
Hematokrit < 30%
PaO2 < 60 mmHg atau saturasi O2 < 90%
Efusi pleura
Umur (tahun)
Umur (tahun–10)
+10
+30
+20
+10
+10
+10
+20
+20
+20
+15
+10
+30
+20
+20
+10
+10
+10
+10
*) Penilaian untuk tingkat keparahan pneumonia kelas II-V: kelas II, 1-70; kelas
III, 71-90; kelas IV, 91-130; kelas V >130.
9

2.1.6 Faktor Risiko
Faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan peningkatan risiko PK,
antara lain:7
a. Usia > 65 tahun.
b. Penyakit kronik (misalnya ginjal dan paru).
c. Mempunyai riwayat diabetes mellitus.
d. Imunosupresi (misalnya karena obat-obatan atau HIV).
e. Ketergantungan alkohol.
f. Penyakit virus yang baru terjadi (misalnya influenza).
g. Malnutrisi
2.1.7 Diagnosis
Tujuannya adalah untuk menegakkan diagnosis, mengidentifikasi
komplikasi, menilai keparahan, dan menentukan klasifikasi untuk terapi empiris
antibiotika yang tepat. Diagnosis pneumonia utamanya didasarkan pada riwayat
penyakit yang lengkap melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaaan
penunjang.
Anamnesis
Keluhan utama yang sering terjadi pada pasien pneumonia adalah sesak
napas, peningkatan suhu tubuh, dan batuk. Pada pasien dengan pneumonia,
keluhan batuk biasanya timbul mendadak dan tidak berkurang setelah meminum
obat batuk yang biasanya tersedia di pasaran. Pada awalnya keluhan batuk tidak
produktif, tapi selanjutnya akan berkembang menjadi batuk produktif dengan
mukus purulen berwarna kekuningan, kehijauan, dan seringkali berbau busuk.
Pasien biasanya mengeluh mengalami demam tinggi dan menggigil. Pada pasien
juga terdapat keluhan nyeri dada, sesak napas, peningkatan frekuensi pernapasan,
lemas, dan nyeri kepala.7
Pemeriksaan fisik
Gambaran klinis biasanya didahului oleh infeksi saluran napas akut bagian
atas selama beberapa hari, kemudian diikuti dengan demam, menggigil, hingga
suhu tubuh kadang-kadang melebihi 40°C. Tanda fisik pneumonia klasik bisa
10

didapatkan sesak napas dan tanda-tanda konsolidasi paru berupa perkusi paru
yang pekak atau redup, ronki nyaring, dan suara pernapasan bronkial. Tanda lain
yang dapat ditemukan adalah sakit tenggorokan, nyeri otot dan sendi, juga disertai
batuk dengan sputum purulen.7
Pemeriksaan penunjang
Pada pemeriksaan laboratorium darah rutin terdapat peningkatan sel darah
putih (leukositosis), biasanya didapatkan jumlah white blood cells (WBC) adalah
15.000-40.000/mm3. Penurunan jumlah WBC (leukopenia) atau normal dapat
disebabkan oleh virus atau mikoplasma atau pada infeksi yang berat sehingga
tidak terjadi respons leukosit, pada lanjut usia, atau lemah. Dalam keadaan
leukopenia, laju endap darah (LED) biasanya meningkat hingga 100/mm3 dan
protein reaktif C mengkonfirmasi adanya infeksi bakteri. Analisis gas darah dapat
mengidentifikasi tingkat hipoksia dan kebutuhan oksigen.7
Kultur darah dapat positif pada 20-25% penderita yang tidak diobati.
Kadang-kadang didapatkan peningkatan kadar ureum darah, akan tetapi kreatinin
masih dalam batas normal.2
Gambaran radiologis pada pneumonia tidak dapat menunjukkan perbedaan
nyata antara infeksi virus dengan bakteri. Pneumonia virus umumnya
menunjukkan gambaran infiltrat intertisial dan hiperinflasi. Pneumonia yang
disebabkan oleh kuman Pseudomonas sering memperlihatkan adanya infiltrat
bilateral atau bronkopneumonia.2
2.1.8 Penatalaksanaan
Penatalaksanaan PK masih merupakan tantangan yang besar bagi para
klinisi. Sebagian besar pasien PK (80%) biasanya diterapi sebagai pasien rawat
jalan, dimana biasanya diberikan regimen antibiotika tunggal. Sedangkan sisanya
sekitar 20% akan memerlukan perawatan di rumah sakit, dimana masih terdapat
perdebatan antara efikasi berbagai pendekatan penatalaksanaan pasien PK yang
menjalani perawatan ini.3
Berdasarkan atas panduan penatalaksanaan pasien dengan PK oleh
American Thoracic Society (ATS), untuk pasien yang memerlukan perawatan di
11

rumah sakit dengan penyakit kardiopulmoner dengan atau tanpa faktor modifikasi,
terapi yang dianjurkan adalah terapi dengan golongan β-lactam (cefotaxim,
ceftriaxon, ampicillin/sulbactam, dosis tinggi ampicillin intravena) yang
dikombinasi dengan makrolide atau doksisiklin oral atau intravena, atau
pemberian fluroquinolon antipneumococcal intravena saja. Begitu juga panduan
penatalaksanaan yang dikeluarkan oleh Infectious Diseases Society of America
(IDSA) menganjurkan pemberian pemberian cephalosporin ditambah makrolide
atau β-lactam/β-lactamase inhibitor ditambah makrolide atau fluroquinolon saja.3-4
Terapi permulaan untuk pasien dengan PK sebagian besar berdasarkan
terapi empiris. Rekomendasi British dan Amerika Utara sebelumnya
merekomendasikan terapi dengan benzyl penicillin, amoxicillin, atau terapi
antibiotika β-lactam yang lain untuk pneumonia yang tidak terkomplikasi.
Penambahan makrolide untuk penatalaksanaan awal tidak direkomendasikan
kecuali terdapat kecurigaan yang tinggi terhadap adanya pneumonia yang
disebabkan karena kuman atipikal. Namun berdasarkan publikasi Amerika Utara,
didapatkan bahwa kombinasi terapi yang terdiri dari antibiotika golongan β-
lactam ditambah makrolide atau monoterapi dengan satu fluoquinolon terbaru
dalam penatalaksanaan awal pasien PK rawat inap yang tidak memerlukan
perawatan ICU, dapat menurunkan mortalitas dan lama perawatan pasien. Untuk
itu, ATS dan IDSA telah merevisi panduannya untuk penatalaksanaan PK, dan
kini merekomendasikan terapi dengan antibiotika golongan β-lactam ditambah
makrolide atau monoterapi dengan satu fluoquinolon untuk semua pasien yang
rawat inap karena PK.3
Masih terdapat perdebatan berdasarkan efikasi dari berbagai jenis
pendekatan penatalaksanaan PK. Dari berbagai macam studi klinis, hanya
setengah kasus agen penyebab dapat diidentifikasi, dimana Streptococcus
pneumoniae merupakan etiologi yang dominan pada kondisi ini. Terlebih lagi
S.pneumoniae merupakan penyebab utama kematian pada pasien dengan PK, yang
mengakibatkan kematian pada sekitar 2/3 kasus. Walaupun mortaliatas akibat
S.pneumoniae telah menurun dalam dekade terakhir, bakteriemik pneumococcal
pneumonia masih bersifat letal, kemungkinan akibat adanya proses penuaan,
12

peningkatan jumlah pasien imunocompromised (HIV/AIDS dan kemoterapi), dan
adanya kondisi komorbid seperti PPOK atau penyakit jantung kongestif.3
Penatalaksanaan yang baik terhadap bakteriemik streptococcal pneumonia
akan secara signifikan menurunkan angka kematian pasien PK. Terdapat isu
penting tentang penggunaan dual terapi meningkatkan outcome yang lebih baik
dibandingkan dengan monoterapi pada pasien PK. Dual terapi yang dimaksud
adalah kombinasi antara regimen yang terdiri dari antibiotika β-lactam, makrolide,
atau fluroquinolon. Sedangkan monoterapi yang dimaksud adalah penggunaan
golongan β-lactam atau fluoroquinolon sebagai agen tunggal.3
Keuntungan dual terapi di atas kemungkinan disebabkan oleh hal-hal
sebagai berikut:
a. Kuman atipikal
Peranan patogen atipikal dalan etiologi PK relatif belum diketahui,
namun merupakan hal yang penting. Laporan terbaru mendapatkan bahwa PK
yang berhubungan dengan patogen atipikal adalah sebanyak 20%. Beberapa
pendapat menganggap bahwa underdiagnosis terhadap koinfeksi dengan
kuman atipikal bertanggung jawab terhadap keuntungan yang diperoleh dari
agen yang mengkover terapi empiris ini.
b. Reistensi terhadap antibitika
Keuntungan survival regimen kombinasi juga dapat dijelaskan akibat
adanya resistensi S.pneumoniae terhadap antibiotika golongan β-lactam.
c. Efek antiinflamasi dari makrolide
Makrolide memiliki efek antiinflamasi. Makrolide dapat menurunkan
produksi sitokin proinflamatori dan ekspresi endotelin-1, menghambat
produksi superoksid, dan menurunkan pneumococcus adherence ke endotel
respiratorius.3
2.1.9 Komplikasi
Dapat terjadi komplikasi pneumonia ekstrapulmoner, misalnya pada
pneumonia pneumokokkus dengan bakteriemi dijumpai pada 10% kasus berupa
meningitis, arthritis, endokarditis, perikarditis, peritonitis, dan empiema.
13

Terkadang dijumpai komplikasi ekstrapulmoner non-infeksius yang
memperlambat resolusi gambaran radiologi paru, antara lain gagal ginjal, gagal
jantung, emboli paru, dan infark miokard akut. Dapat terjadi komplikasi lain
berupa acute respiratory distress syndrome (ARDS), gagal organ jamak, dan
komplikasi lanjut berupa pneumonia nosokomial (PN).7
2.1.10 Prognosis
Kejadian PK di Amerika Serikat adalah 3,4-4 juta kasus per tahun, dan
20% diantaranya perlu dirawat di RS. Secara umum, angka kematian pneumonia
oleh pneumokokkus adalah sebesar 5%, namun dapat meningkat pada lanjut usia
dengan kondisi yang buruk. Pneumonia dengan influenza di Amerika Serikat
merupakan penyebab kematian terbesar ke-6 dengan kejadian sebesar 59%.
Sebagian besar pada lanjut usia, yaitu sebesar 89%. Mortalitas pasien PK yang
dirawat di ICU adalah sebesar 20%. Mortalitas yang tinggi ini berkaitan dengan
faktor modifikasi yang ada pada pasien.7
2.2 Hipertensi
2.2.1 Definisi
Sampai saat ini hipertensi masih tetap menjadi masalah di seluruh dunia,
terutama pada lanjut usia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain
meningkatnya prevalensi hipertensi, banyaknya pasien hipertensi yang belum
mendapat pengobatan maupun yang sudah diobati tetapi tekanan darahnya belum
mencaai target, serta adanya penyakit penyerta dan komplikasi yang dapat
meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Hipertensi adalah keadaan tekanan darah
sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg.10,11
2.2.2 Epidemiologi
Jumlah penduduk berusia di atas 60 tahun di Indonesia pada tahun 2010
mengalami kenaikan sebesar 400%, sehingga jumlahnya melebihi jumlah bayi di
bawah lima tahun (balita). Lanjut usia membawa konsekuensi meningkatnya
berbagai penyakit kardiovaskular, infeksi, dan stroke. Hipertensi merupakan
14

penyebab meningkatnya prevalensi gagal jantung dan stroke pada lanjut usia. Data
epidemiologis menunjukkan bahwa dengan makin meningkatnya populasi lanjut
usia, maka jumlah pasien dengan hipertensi kemungkinan besar juga akan
bertambah, dimana hipertensi sistolik sistolik maupun kombinasi hipertensi
sistolik dan diastolik sering timbul pada lebih dari separuh orang yang berusia di
atas 65 tahun. Selain itu, laju pengendalian tekanan darah yang dahulu terus
meningkat, dalam dekade terakhir tidak menunjukkan kemajuan lagi (pola kurva
mendatar), dan pengendalian tekanan darah ini hanya mencapai 34% dari seluruh
pasien hipertensi.9
Sampai saat ini, data hipertensi yang lengkap sebagian besar berasal dari
negara-negara yang sudah maju. Data dari The National Health and Nutrition
Examination Survey (NHANES) yang dilaksanakan 1999-2000 didapatkan bahwa
angka prevalensi pada populasi dewasa adalah sekitar 29-31%, yang berarti
terdapat 58-65 juta orang hipertensi di Amerika, dan terjadi peningkatan sebesar
15 juta dari data NHANES III yang dilaksanakan tahun 1988-1991.10,11 Prevalensi
hipertensi di Indonesia juga cukup tinggi. Hasil survei dari Multinational
Monitoring of Trends and Determinant in Cardiovascular Disease pada tahun
1993, prevalensi di Indonesia mencapai 16,9%. Menurut laporan dari Survei
Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995, prevalensi hipertensi pada dewasa
adalah 7,4% pada pria dan 9,1% pada wanita. Hipertensi primer atau esensial
merupakan 95% dari seluruh kasus hipertensi.9-11
2.2.3 Klasifikasi
Berdasarkan etiologinya, hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Hipertensi primer atau esensial
Hipertensi primer atau juga disebut hipertensi esensial adalah hipertensi
yang tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik. Sekitar 90% penderita
hipertensi menderita jenis hipertensi ini. Penyebab yang mendasari hipertensi
primer masih belum diketahui, namun sebagian besar disebabkan oleh
ketidaknormalan tertentu pada arteri. Penderita hipertensi primer memiliki
resistensi yang semakin tinggi (kekakuan atau kekurangan elastisitas) pada
15

arteri-arteri yang kecil yang paling jauh dari jantung (arteri periferal atau
arterioles), dimana hal ini seringkali berkaitan dengan faktor-faktor genetik,
obesitas, kurang olahraga, asupan garam berlebih, bertambahnya usia, dan lain-
lain. Secara umum faktor-faktor tersebut antara lain:11
1. Faktor genetika (riwayat keluarga)
Hipertensi merupakan suatu kondisi yang bersifat menurun dalam suatu
keluarga. Anak dengan orang tua hipertensi memiliki kemungkinan dua kali
lebih besar untuk menderita hipertensi daripada anak dengan orangtua yang
tekanan darahnya normal.
2. Ras
Orang-orang afro yang hidup di masyarakat barat mengalami hipertensi
secara merata yang lebih tinggi daripada orang berkulit putih. Hal ini
kemungkinan disebabkan karena tubuh mereka mengolah garam secara
berbeda.
3. Usia
Hipertensi lebih umum terjadi berkaitan dengan usia, khususnya pada
masyarakat yang banyak mengkonsumsi garam. Wanita premenopause
cenderung memiliki tekanan darah yang lebih tinggi daripada pria pada usia
yang sama, meskipun perbedaan diantara jenis kelamin kurang tampak
setelah usia 50 tahun. Penyebabnya, sebelum menopause, wanita relatif
terlindungi dari penyakit jantung oleh hormon estrogen. Kadar estrogen
menurun setelah menopause dan wanita mulai menyamai pria dalam hal
penyakit jantung.
4. Jenis kelamin
Pria kemungkinan lebih banyak menderita hipertensi daripada wanita.
Hipertensi berdasarkan jenis kelamin ini dapat pula dipengaruhi oleh faktor
psikologis. Pada pria seringkali dipicu oleh perilaku tidak sehat (merokok,
kelebihan berat badan), depresi dan rendahnya status pekerjaan, sedangkan
pada wanita lebih berhubungan dengan pekerjaan yang mempengaruhi
faktor psikis kuat.
16

5. Stress psikis
Stress meningkatkan aktivitas saraf simpatis, dimana peningkatan ini akan
mempengaruhi meningkatnya tekanan darah secara bertahap. Apabila stress
berkepanjangan dapat berakibat tekanan darah menjadi tetap tinggi. Secara
fisiologis apabila seseorang stress, maka kelenjar pituitari otak akan
menstimulus kelenjar endokrin untuk menghasilkan hormon adrenalin dan
hidrokortison ke dalam darah sebagai bagian homeostasis tubuh.
6. Obesitas
Pada orang yang obesitas akan terjadi peningkatan kerja pada jantung untuk
memompa darah agar dapat menggerakkan beban berlebih dari tubuh
tersebut. Berat badan yang berlebihan menyebabkan bertambahnya volume
darah dan perluasan sistem sirkulasi. Mereduksi berat badan hingga 5-10%
dari bobot total tubuh dapat menurunkan resiko kardiovaskular secara
signifikan.
7. Asupan garam
Ion natrium mengakibatkan retensi air, sehingga volume darah bertambah
dan menyebabkan daya tahan pembuluh meningkat dan memperkuat efek
vasokonstriksi noradrenalin. Secara statistika, ternyata bahwa pada
kelompok penduduk yang mengonsumsi terlalu banyak garam terdapat lebih
banyak hipertensi daripada orang-orang yang memakan hanya sedikit
garam.
8. Rokok
Nikotin dalam tembakau adalah penyebab tekanan darah meningkat karena
nikotin terserap oleh pembuluh darah yang kecil dalam paru-paru dan
disebarkan ke seluruh aliran darah. Hanya dibutuhkan waktu 10 detik bagi
nikotin untuk sampai ke otak. Otak bereaksi terhadap nikotin dengan
memberikan sinyal kepada kelenjar adrenal untuk melepaskan efinefrin
(adrenalin). Hormon yang sangat kuat ini menyempitkan pembuluh darah,
sehingga memaksa jantung untuk memompa lebih keras di bawah tekanan
yang lebih tinggi.
17

9. Konsumsi alkohol
Alkohol memiliki pengaruh terhadap tekanan darah, dan secara keseluruhan
semakin banyak alkohol yang diminum semakin tinggi tekanan darah. Tapi
pada orang yang tidak meminum minuman keras memiliki tekanan darah
yang agak lebih tinggi daripada yang meminum dengan jumlah yang sedikit.
b. Hipertensi sekunder
Hipertensi sekunder memiliki patogenesis yang spesifik. Hipertensi
sekunder dapat terjadi pada individu dengan usia sangat muda tanpa disertai
riwayat hipertensi dalam keluarga. Individu dengan hipertensi pertama kali
pada usia di atas 50 tahun atau yang sebelumnya diterapi tapi mengalami
refrakter terhadap terapi yang diberikan mungkin mengalami hipertensi
sekunder. Penyebab hipertensi sekunder antara lain penggunaan estrogen,
penyakit ginjal, hipertensi vaskular ginjal, hiperaldosteronisme primer,
sindroma Cushing, koarktasio aorta, kehamilan, dan penggunaan obat-obatan.11
Pada tahun 2003, The Seventh Report of The Joint National Commitee on
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC-
VII) mengeluarkan batasan baru untuk klasifikasi tekanan darah bagi orang
dewasa. Klasifikasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3. Klasifikasi hipertensi berdasarkan The Seventh Report of The Joint National Commitee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (JNC-VII)7
Klasifikasi hipertensi Sistolik (mmHg) Diastolik (mmHg)
Normal
Pre-hipertensi
Hipertensi tingkat 1
Hipertensi tingkat 2
<120
120-139
140-159
≥160
<80
80-89
90-99
≥100
Kelompok pre-hipertensi tidak digolongkan sebagai penyakit, namun
digunakan sebagai indikator bahwa seseorang yang masuk dalam kelompok ini
memiliki risiko tinggi untuk terkena hipertensi, penyakit jantung koroner, dan
stroke, sehingga dokter maupun penderita dapat mengantisipasi kondisi ini lebih
18

dini sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih parah. Individu dengan pre-
hipertensi tidak memerlukan medikasi, tapi dianjurkan untuk melakukan
modifikasi gaya hidup sehat untuk mencegah peningkatan tekanan darahnya.
Modifikasi gaya hidup sehat berupa penurunan berat badan (obesitas), olahraga,
diet rendah garam, berhenti merokok, dan membatasi minum alkohol.10
2.2.4 Patogenesis
Hipertensi primer adalah penyakit multifaktorial yang timbul terutama
karena interaksi antara faktor-faktor risiko tertentu. Faktor-faktor risiko yang
mendorong timbulnya kenaikan tekanan darah tersebut adalah:10
a. Faktor risiko, seperti diet dan asupan garam, stres, ras, obesitas, merokok, dan
genetik.
b. Sistem saraf simpatis
- Tonus simpatis
- Variasi diurnal
c. Keseimbangan antara modulator vasodilatasi dan vasokonstriksi: endotel
pembuluh darah berperan utama, tetapi remodeling dari endotel, otot polos, dan
interstisium juga memberikan konstribusi akhir.
d. Pengaruh sistem otokrin setempat yang berperan pada sistem renin,
angiotensin, dan aldosteron.1
Kaplan menggambarkan beberapa faktor yang berperan dalam
pengendalian tekanan darah yang mempengaruhi rumus dasar:
Tekanan Darah = Curah Jantung x Tahanan Perifer (Gambar 1)1
19

Hipertensi = Peningkatan CJ dan/atau Peningkatan TP
Gambar 1. Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Pengendalian Tekanan Darah
2.2.5 Tanda dan Gejala
Individu dengan tekanan darah yang tinggi kadang tidak menampakan
gejala sampai bertahun-tahun. Gejala akan timbul bila telah ada kerusakan
vaskular dengan manifestasi yang khas sesuai sistem organ yang divaskularisasi
oleh pembuluh darah bersangkutan. Perubahan patologis pada ginjal dapat
bermanifestasi sebagai nokturia (peningkatan urinasi pada malam hari) dan
azetoma (peningkatan nitrogen urea darah (BUN) dan kreatinin). Keterlibatan
pembuluh darah otak dapat menimbulkan stroke atau serangan iskemik transien
yang bermanifestasi sebagai paralisis sementara pada satu sisi (hemiplegia) atau
gangguan tajam penglihatan.11
20
Asupangaram
berlebih
Jumlahnefron
berkurang
Perubahangenetik
Stres Obesitas Bahan-bahanyang berasaldari endotel
Retensinatriumginjal
Penurunanpermukaan
filtrasi
Aktivitasberlebih
saraf simpatis
Reninangiotensin
berlebih
Perubahanmembran sel
Volume cairan
Hiper-insulinemia
Konstriksi vena
Preload Kontraktilitas Konstriksifungsional
Hipertrofistruktural
TEKANAN DARAH = CURAH JANTUNG x TEKANAN PERIFER
Otoregulasi

Sebagian besar gejala klinis timbul setelah mengalami hipertensi bertahun-
tahun, berupa nyeri kepala saat terjaga, kadang-kadang disertai mual dan muntah
akibat peningkatan tekanan darah intrakranial, penglihatan kabur akibat kerusakan
retina, ayunan langkah yang tidak mantap karena kerusakan susunan saraf pusat,
nokturia karena peningkatan aliran darah ginjal dan filtrasi glomerolus, edema
dependen, dan pembengkakan akibat peningkatan tekanan kapiler.11
Sekitar 50% penderita hipertensi tidak menyadari bahwa tekanan darah
mereka meninggi. Gejala baru timbul setelah terjadi komplikasi pada organ target,
seperti ginjal, mata, sakit kepala, gangguan fungsi ginjal, gangguan penglihatan,
gangguan serebral, atau gejala akibat peredaran pembuluh darah otak berupa
kelumpuhan, gangguan kesadaran bahkan sampai koma.11
2.2.6 Penatalaksanaan
Tujuan pengobatan pasien hipertensi adalah mencapai target tekanan darah
<140/90 mmHg, penurunan morbiditas dan mortalitas kardivaskular, serta
menghambat laju penyakit ginjal proteinuria. Penatalaksanaan hipertensi terdiri
dari terapi non-farmakologis dan farmakologis. Terapi non-farmakologis harus
dilaksanakan oleh semua pasien hipertensi dengan tujuan menurunkan tekanan
darah dan mengendalikan faktor-faktor risiko serta penyakit penyerta lainnya.
Terapi non-farmakologis adalah dengan modifikasi gaya hidup pasien, antara
lain:9-12
a. Menurunkan berat badan sampai batas ideal pada pasien hipertensi yang
mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.
b. Mengubah pola makan, yaitu mengurangi asupan garam sampai kurang dari 3
gram natrium (disertai dengan asupan kalsium, magnesium, dan kalium yang
cukup), meningkatkan asupan buah dan sayur, dan mengurangi asupan lemak,
serta mengurangi konsumsi alkohol.
c. Olah raga teratur yang tidak terlalu berat. Pasien hipertensi primer tidak perlu
membatasi aktivitasnya selama tekanan darahnya terkendali.
d. Berhenti merokok karena merokok dapat merusak jantung dan sirkulasi darah
dan meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke.
21

Jenis-jenis obat antihipertensi untuk terapi farmakologis yang dianjurkan
oleh JNC-VII adalah:9-12
a. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACE-inhibitor) menyebabkan
penurunan tekanan darah dengan cara melebarkan arteri.
b. Angiotensin II Receptor Blocker (ARB) menyebabkan penurunan tekanan
darah dengan suatu mekanisme yang mirip dengan ACE-inhibitor.
c. Beta Blocker yang menghambat efek sistem saraf simpatis. Sistem saraf
simpatis adalah sistem saraf yang dengan segera akan memberikan respon
terhadap stres, dengan cara meningkatkan tekanan darah.
d. Calsium Channel Blocker (CCB) atau Calsium antagonist menyebabkan
melebarnya pembuluh darah dengan mekanisme yang benar-benar berbeda.
e. Diuretik, terutama golongan Thiazide atau Aldosterone antagonist. Diuretik
membantu ginjal membuang garam dan air yang akan mengurangi volume
cairan di seluruh tubuh sehingga menurunkan tekanan darah. Diuretik juga
menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Diuretik akan menyebabkan
hilangnya kalium melalui air, sehingga harus diberikan tambahan kalium atau
obat penahan kalium.
2.2.7 Pencegahan
Perawatan penderita hipertensi pada umumnya dilakukan oleh keluarga
dengan memperhatikan pola hidup dan menjaga psikis dari anggota keluarga yang
menderita hipertensi. Pengaturan pola hidup sehat sangat penting pada pasien
hipertensi untuk mengurangai komplikasi dari hipertensi. Adapun cakupan pola
hidup sehat antara lain berhenti merokok, mengurangi kelebihan berat badan,
menghindari alkohol, modifikasi diet, mengurangi stres, dan olahraga teratur.9-11
Merokok sangat besar peranannya meningkatkan tekanan darah, hal ini
disebabkan oleh nikotin yang terdapat di dalam rokok memicu hormon adrenalin
yang dapat menyebabkan tekanan darah meningkat. Nikotin diserap oleh
pembuluh-pembuluh darah di dalam paru dan diedarkan ke seluruh aliran darah
lainnya sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah. Hal ini menyebabkan kerja
jantung semakin meningkat untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui
22

pembuluh darah yang sempit. Dengan berhenti merokok, tekanan darah akan
turun secara perlahan. Selain itu, merokok juga akan mengakibatkan obat yang
dikonsumsi tidak akan bekerja secara optimal dan menurunkan efektivitas.11
Mengurangi berat badan dapat menurunkan risiko diabetes, penyakit
kardiovaskular, dan kanker. Secara umum, semakin berat tubuh semakin tinggi
tekanan darah. Jika menerapkan pola makan seimbang, maka dapat mengurangi
berat badan dan menurunkan tekanan darah dengan cara yang terkontrol.10
Alkohol dalam darah merangsang adrenalin dan hormon-hormon lain yang
membuat pembuluh darah menyempit atau menyebabkan penumpukan natrium
dan air. Minum-minuman yang beralkohol berlebih juga dapat menyebabkan
kekurangan gizi, yaitu penurunan kadar kalsium. Mengurangi alkohol dapat
menurunkan tekanan sistolik 10 mmHg dan diastolik 7 mmHg.10
Modifikasi diet sangat penting pada pasien hipertensi. Tujuan utama dari
pengaturan diet hipertensi adalah mengatur tentang makanan sehat yang dapat
mengontrol tekanan darah dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Secara
garis besar, ada empat macam diet untuk mempertahankan tekanan darah, yaitu
diet rendah garam, diet rendah kolestrol, lemak terbatas serta tinggi serat, dan
rendah kalori bila kelebihan berat badan.10
Diet rendah garam diberikan kepada pasien dengan edema atau asites serta
hipertensi. Tujuan diet rendah garam adalah untuk menurunkan tekanan darah dan
untuk mencegah edema dan penyakit jantung. Diet rendah garam bukan hanya
membatasi konsumsi garam dapur, tetapi juga mengkonsumsi makanan rendah
sodium atau natrium. Oleh karena itu, hal yang sangat penting untuk diperhatikan
dalam melakukan diet rendah garam adalah komposisi makanan yang harus
mengandung cukup zat-zat gizi, baik kalori, protein, mineral maupun vitamin,
serta rendah sodium dan natrium.10
Sumber sodium antara lain adalah makanan yang mengandung soda kue,
baking powder, monosodium glutamat, pengawet makanan atau natrium benzoat
(biasanya terdapat di dalam saos, kecap, selai, jelly), makanan yang dibuat dari
mentega, serta obat yang mengandung natrium (obat sakit kepala). Bagi pasien
23

hipertensi, biasakan untuk penggunaan obat dikonsultasikan dengan dokter
terlebih dahulu.11
Diet rendah kolestrol dan lemak terbatas. Di dalam tubuh terdapat tiga
bagian lemak, yaitu kolestrol, trigliserida, dan fosfolipid. Tubuh memperoleh
kolestrol dari makanan sehari-hari dan dari hasil sintesis dalam hati. Kolestrol
dapat berbahaya jika dikonsumsi lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh
tubuh. Peningkatan kolestrol dapat terjadi karena terlalu banyak mengkonsumsi
makanan yang mengandung kolestrol tinggi dan tubuh akan mengkonsumsi
sekitar 25-50% dari setiap makanan.11
Diet tinggi serat sangat penting pada pasien hipertensi. Serat kasar (crude
fiber) banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan, sedangkan serat makanan
terdapat pada makanan karbohidrat, yaitu kentang, beras, singkong, dan kacang
hijau. Serat kasar dapat berfungsi mencegah penyakit tekanan darah tinggi karena
serat kasar mampu mengikat kolestrol maupun asam empedu dan selanjutnya
dibuang bersama kotoran. Keadaan ini dapat dicapai jika makanan yang
dikonsumsi mengandung serat kasar yang cukup tinggi.10
Diet rendah kalori dianjurkan bagi orang yang kelebihan berat badan.
Kelebihan berat badan atau obesitas akan berisiko tinggi terkena hipertensi.
Demikian juga dengan orang yang berusia 40 tahun akan mudah terkena
hipertensi. Dalam perencanaan diet, perlu diperhatikan hal-hal berikut:11
1. Asupan kalori dikurangi sekitar 25% dari kebutuhan energi atau 500 kalori
untuk penurunan 500 gram atau 0,5 kg berat badan per minggu.
2. Menu makanan harus seimbang dan memenuhi kebutuhan zat gizi.
Stres tidak menyebabkan hipertensi yang menetap, tetapi stres berat dapat
memicu kenaikan tekanan darah yang bersifat sementara yang sangat tinggi. Jika
periode stres sering terjadi, maka akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah,
jantung, dan ginjal.10
Manfaat olah raga yang sering disebut olah raga isotonik seperti jalan
kaki, jogging, berenang, dan bersepeda mampu meredam hipertensi. Olah raga
isotonik mampu menurunkan hormon noradrenalin dan hormon-hormon lain yang
24

menyebabkan naiknya tekanan darah. Olah raga isometrik seperti angkat beban
harus dihindari karena justru dapat menaikkan tekanan darah.10,11
2.2.8 Komplikasi
Komplikasi yang dapat terjadi akibat hipertensi antara lain:10,11
a. Stroke
Stroke dapat timbul akibat perdarahan tekanan tinggi di otak atau akibat
embolus yang terlepas dari pembuluh non-otak yang terpajan tekanan tinggi.
Stroke dapat terjadi pada hipertensi kronis apabila arteri-arteri yang
memperdarahi otak mengalami hipertropi dan menebal, sehingga aliran darah
ke daerah-daerah yang diperdarahinya berkurang. Arteri-arteri otak yang
mengalami aterosklerosis dapat melemah sehingga meningkatkan
kemungkinan terbentuknya aneurisma. Gejala serangan stroke adalah sakit
kepala secara tiba-tiba, seperti orang bingung, salah satu bagian tubuh terasa
lemah atau sulit digerakkan (misalnya wajah, mulut, lengan terasa kaku, tidak
dapat berbicara secara jelas), serta penurunan kesadaran secara mendadak.
b. Infark miokard
Infark miokard dapat terjadi apabila arteri koroner yang mengalami
aterosklerosis tidak dapat menyuplai cukup oksigen ke miokardium, atau
apabila terbentuk trombus yang menghambat aliran darah melalui pembuluh
darah tersebut. Karena hipertensi kronis dan hipertensi ventrikel, maka
kebutuhan oksigen miokardium mungkin tidak dapat terpenuhi dan dapat
terjadi iskemia jantung yang akan menyebabkan infark. Demikian juga
hipertrofi ventrikel dapat menimbulkan perubahan-perubahan waktu hantaran
listrik melintasi ventrikel sehingga terjadi disritmia, hipoksia jantung, dan
peningkatan risiko pembentukan bekuan.
c. Gagal ginjal
Gagal ginjal dapat terjadi kerusakan progresif akibat tekanan tinggi pada
kapiler-kapiler ginjal dan glomerolus. Dengan rusaknya glomerolus, darah
akan mengalir ke unit-unit fungsional ginjal, nefron akan terganggu dan dapat
berlanjut menjadi hipoksia dan kematian. Dengan rusaknya membran
25

glomerolus, protein akan keluar melalui urin sehingga tekanan osmotik koloid
plasma berkurang, yang menyebabkan edema yang sering dijumpai pada
hipertensi kronis.
d. Gagal jantung
Gagal jantung adalah kegagalan jantung dalam memompa darah ke seluruh
tubuh sehingga mengakibatkan cairan terkumpul di paru, kaki, dan jaringan
lain (edema). Cairan di dalam paru-paru akan menyebabkan sesak napas,
timbunan cairan di tungkai menyebabkan kaki bengkak.
26

BAB IIILAPORAN KASUS
3.1 Identitas Pasien
No. Medical Record : 01.58.62.98
Nama Pasien : MN
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Gianyar, 31 Desember 1935
Umur : 76 tahun
Alamat : Banjar Medahan Kemenuh Gianyar
Agama : Hindu
Suku : Bali
Bangsa : Indonesia
Pendidikan : Tamat SD
Status Perkawinan : Janda
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tanggal Rawat Inap : 11 September 2012
Tanggal Pemeriksaan : 14 September 2012
3.2 Anamnesis
Keluhan Utama : Batuk
Riwayat Penyakit Sekarang
Pasien dikonsulkan oleh teman sejawat Neurologi karena pasien
mengeluh batuk. Batuk dikatakan sudah muncul sejak 2 bulan sebelum masuk
rumah sakit, namun dirasakan bertambah berat saat hari ke-2 dirawat di
RSUP Sanglah. Batuk dirasakan pasien terus-menerus sepanjang hari,
kadang-kadang disertai dahak kental berwarna putih. Volume dahak yang
keluar sekali batuk sekitar ¼ hingga ½ sendok makan. Batuk dengan dahak
berdarah disangkal oleh pasien. Saat pemeriksaan, pasien masih batuk tanpa
dahak namun dikatakan frekuensinya sudah berkurang.
27

Batuk tersebut juga disertai dengan sesak napas. Sesak napas timbul
secara mendadak saat batuk. Sesak mulanya terasa ringan, tidak pernah hilang
dan semakin lama dirasakan semakin memberat. Sesak napas dirasakan terus-
menerus saat pasien menarik napas dalam-dalam dan memburuk saat batuk
kuat. Sesak napas dirasakan seperti tertekan sampai membuat pasien
mengeluh sulit tidur. Sesak tidak membaik dengan perubahan posisi. Sesak
napas juga membuat pasien menjadi lemas. Saat pemeriksaan, pasien
mengatakan sesaknya sudah berkurang.
Pasien juga mengeluh panas badan sejak hari ke-2 dirawat di RSUP
Sanglah yang muncul bersamaan dengan keluhan batuk yang dialami pasien.
Panas badan terjadi mendadak dan dirasakan terus-menerus, baik siang
maupun malam. Panas badan dikatakan membaik dengan obat penurun panas,
dan pasien merasa sudah tidak panas saat pemeriksaan.
Pasien menyangkal adanya keluhan mual dan muntah. Pasien juga
menyangkal adanya penurunan nafsu makan dan berat badan, serta
berkeringat pada malam hari. BAK pasien dikatakan biasa dengan frekuensi
berkemih sekitar 4-5 kali dalam sehari, volume tiap berkemih ± ¾ hingga 1
gelas berwarna jernih kekuningan. BAB pasien juga dikatakan biasa,
frekuensi rata-rata sekali sehari, warna kecokelatan, dan konsistensi padat.
Riwayat Penyakit Sebelumnya
Sebelumnya, pasien masuk rumah sakit karena keluhan jatuh dan
pingsan saat melakukan aktivitas di rumah. Jatuhnya dikatakan mendadak dan
pasien pingsan sampai tiba di RSUP Sanglah. Setiba di RSUP Sanglah,
pasien sudah sadar. Assesmen dari teman sejawat Neurologi adalah acute
confusional state (ACS) et causa meningitis bakteri dd TB.
Pasien mengatakan sering mengalami batuk terutama saat bangun
tidur dengan dahak kental sebelum keluhan saat ini muncul. Batuk dirasakan
sudah muncul sejak 2 bulan terakhir, namun terkadang hilang dengan
sendirinya. Terkadang pasien juga mengeluh sesak saat batuk muncul, namun
tidak pernah separah yang dirasakan sekarang.
28

Keluarga pasien mengatakan pasien memiliki riwayat tekanan darah
tinggi sejak 10 tahun yang lalu tanpa keluhan dan obatnya tidak diminum
secara rutin.
Riwayat penyakit lain seperti kencing manis, penyakit jantung, asma
disangkal oleh pasien.
Riwayat Pengobatan
Sebelum masuk rumah sakit, pasien rutin ke Puskesmas di Negara
untuk memeriksakan keluhan batuknya. Pasien diberikan obat batuk sirup,
namun pasien lupa nama obatnya.
Pasien juga memperoleh obat hipertensi, namun tidak diminum secara
teratur.
Riwayat Penyakit Keluarga
Tidak ada anggota keluarga pasien yang mengalami keluhan yang
sama seperti pasien. Riwayat keluarga dengan batuk kronis disangkal.
Riwayat tekanan darah tinggi, asma, alergi obat, penyakit jantung, dan ginjal
pada keluarga disangkal.
Riwayat Pribadi dan Sosial
Pasien dulunya adalah seorang petani, namun saat ini pekerjaan
tersebut tidak dilakukan lagi mengingat usia pasien yang sudah semakin tua.
Pasien merupakan janda setelah suaminya meninggal, serta sudah memiliki 2
orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kini pasien tinggal sendiri di
rumahnya di Negara, sedangkan anak-anaknya tinggal di rumahnya masing-
masing di luar Negara. Riwayat merokok dan mengkonsumsi alkohol
disangkal oleh pasien.
29

3.3 Riwayat Medis
1. Keluhan utama : Batuk
2. Keluhan penyerta
a. Pusing-pusing : Tidak
b. Nyeri kepala : Tidak
c. Kesadaran menurun : Ya, 1 hari sebelum MRS
d. Selera makan berubah : Tidak
e. Berat badan menurun cepat : Tidak
f. Demam : Ya, selama 1 hari di RS
g. Sulit tidur : Ya, selama di RS
h. Mudah marah / tersinggung : Tidak
i. Sakit tenggorokan : Tidak
j. Gangguan pendengaran : Ya, sejak 5 tahun yg lalu
k. Gangguan penglihatan : Ya, sejak 5 tahun yg lalu
l. Batuk / pilek / influenza : Ya, sejak 1 bulan yg lalu
m. Batuk-batuk lama : Ya, sejak 1 bulan yg lalu
n. Sesak napas : Ya, saat dirawat di RS
o. Sakit gigi / lidah / gusi : Tidak
p. Mual / perut perih/ sakit maag : Tidak
q. Mencret / diare : Tidak
r. BAB berdarah : Tidak
s. Mengompol : Tidak
t. Jatuh : Ya, 1 hari sebelum MRS
u. Sakit tulang sendi : Tidak
v. Lainnya : Tidak
3. Riwayat penyakit sekarang
Batuk
4. Riwayat penyakit dahulu
a. Gangguan pembuluh darah otak / stroke : Tidak
b. Katarak : Tidak
c. Nyeri jantung (Angina) : Tidak
30

d. Serangan jantung IMA (MCI) : Tidak
e. Paru-paru (TBC/PPOK/Asma) : Tidak
f. Kolesterol tinggi : Tidak
g. Trigliserida tinggi : Tidak
h. Kegemukan (obesitas) : Tidak
i. Kencing manis / diabetes melitus : Tidak
j. Tekanan darah tinggi : Ya, sejak 10 tahun yg lalu
k. Batu saluran kencing : Tidak
l. Prostat : Tidak
m. Sakit ginjal (ISK/CRF) : Tidak
n. Tulang keropos / osteoporosis : Tidak
o. Rematik / osteoatritis : Tidak
p. Gout pirai : Tidak
q. Kurang darah / anemia : Tidak
r. Kanker : Tidak
s. Gangguan lambung : Tidak
t. Sakit liver : Tidak
u. Batu empedu : Tidak
v. Lainnya : Tidak
5. Riwayat pembedahan : Tidak
6. Riwayat inap rumah sakit : Tidak
7. Riwayat kesehatan lain : Tidak
8. Riwayat alergi : Tidak
9. Obat obatan saat ini
a. Dengan resep dokter : Ya, pasien lupa nama obat
b. Tanpa resep dokter : Tidak
10. Riwayat sosial-kemasyarakatan-keagamaan
a. Rekreasi : Jarang
b. Kegiatan keagamaan : Sering
c. Silahturahmi dengan keluarga : Jarang
d. Silahturahmi dengan sesama lansia : Jarang
31

e. Olah raga : Tidak
f. Lainnya : Tidak
11. Analisis finansial
a. Pekerjaan utama sebelum usia 65 tahun : Petani
b. Menerima pensiun : Tidak
c. Pekerjaan saat ini : Tidak
d. Penghasilan rata-rata per bulan : -
e. Menerima bantuan dalam bentuk uang : Ya
f. Menerima bantuan selain uang : Ya
g. Masih menanggung orang lain : Tidak
h. Penghasilan cukup untuk pengeluaran : -
3.4 Anamnesis Sistem
1. Keadaan umum : Baik
2. Sistem kardiovaskular
a. Nyeri / rasa berat di dada : Tidak
b. Sesak nafas pada waktu kerja : Tidak
c. Terbangun tengah malam karena sesak : Tidak
d. Sesak saat berbaring tanpa bantal : Tidak
e. Bengkak pada kaki / tungkai : Tidak
3. Pulmo
a. Sesak napas : Akut
b. Demam : Akut
c. Batuk berdahak / kering : Kronik
4. Saluran cerna
a. Nafsu makan menurun : Tidak
b. Berak hitam : Tidak
c. Sakit perut : Tidak
d. Mencret : Tidak
e. Perut terasa kembung : Tidak
f. BAB berdarah : Tidak
32

5. Saluran kencing
a. Gangguan BAK : Tidak
b. Nyeri BAK : Tidak
c. Pancaran air seni kurang : Tidak
d. Menetes : Tidak
e. Bangun malam karena BAK : Tidak
6. Hematologi
a. Mudah timbul lebam kulit : Tidak
b. Bila luka, perdarahan lambat berhenti : Tidak
c. Benjolan (di tempat KGB) : Tidak
7. Rematologi
a. Kekakuan sendi : Tidak
b. Bengkak sendi : Tidak
c. Nyeri otot : Tidak
8. Endokrin
a. Benjolan di leher depan samping : Tidak
b. Gemetaran : Tidak
c. Lebih suka udara dingin : Tidak
d. Banyak keringat : Tidak
e. Lekas lelah / lemas : Tidak
f. Rasa haus bertambah : Tidak
g. Mudah mengantuk : Tidak
h. Lesu, lelah, letih, lemah : Tidak
i. Tidak tahan dingin : Tidak
9. Neurologi
a. Pusing / Sakit kepala : Tidak
b. Kesulitan mengingat sesuatu : Tidak
c. Pingsan sesaat : Akut
d. Gangguan penglihatan : Kronik
e. Gangguan pendengaran : Kronik
f. Rasa baal / kesemutan anggota badan : Tidak
33

g. Kesulitan tidur : Akut
h. Kelemahan anggota tubuh : Tidak
i. Lumpuh : Tidak
j. Kejang-kejang : Tidak
10. Jiwa
a. Sering lupa : Tidak
b. Kelakuan aneh : Tidak
c. Mengembara : Tidak
d. Murung : Tidak
e. Sering menangis : Tidak
f. Mudah tersinggung : Tidak
3.5 Penapisan Status Fungsional
a. ADL Barthel (BAI)
No. Fungsi Skor Keterangan
1 Mengontrol BAB
0 Inkontinen/tak teratur (perlu enema)
1 Kadang-kadang inkontinen (1 x seminggu)
2 Kontinen teratur
2 Mengontrol BAK
0 Inkontinen/pakai kateter dan tak terkontrol
1 Kadang-kadang inkontinen (max 1 x 24 jam)
2 Kontinen teratur
3
Membersihkan diri (lap
muka, sisir rambut, sikat
gigi)
0 Butuh pertolongan orang lain
1 Mandiri
4
Penggunaan toilet pergi ke
dalam dari WC (melepas,
memakai celana, menyeka,
menyiram)
0 Tergantung pertolongan orang lain
1Perlu pertolongan beberapa aktivitas tetapi dapat
mengerjakan sendiri aktivitas yang lain
2 Mandiri
5 Makan
0 Tidak mampu
1 Perlu seseorang menolong memotong makan
2 Mandiri
6 Berpindah tempat dari
tidur ke duduk
0 Tidak mampu
1 Perlu banyak bantuan untuk bisa duduk (2 orang)
34

2 Bantuan minimal 1 orang
3 Mandiri
7 Mobilisasi/berjalan
0 Tidak mampu
1 Bisa berjalan dengan kursi roda
2 Berjalan dengan bantuan satu orang
3 Mandiri
8Berpakaian (memakai
baju)
0 Tergantung orang lain
1 Sebagain dibantu (misal mengancing baju)
2 Mandiri
9 Naik turun tangga
0 Tidak mampu
1 Butuh pertolongan orang lain
2 Mandiri (naik turun)
10 Mandi0 Tergantung orang lain
1 Mandiri
Total Skor 20
Skor ADL (BAI)
20 : Mandiri
12 – 19 : Ketergantungan ringan
9 – 1 : Ketergantungan sedang
5 – 8 : Ketergantungan berat
0 – 4 : Ketergantungan total
Total skor = 20 (Mandiri)
b. IADL
No. AktivitasIndependen (tidak perlu
bantuan orang lain) Nilai = 0
Dependen (perlu bantuan
orang lain) Nilai = 1Nilai
1 Telepon
Mengoperasikan telepon
sendiri
Mencari dan menghubungi
nomer
Menghubungi beberapa
nomor yang diketahui
Menjawab telepon tetapi
tidak menghubungi
Tidak bisa
menggunakan telepon
sama sekali
0
35

2 Belanja
Mengatur semua kebutuhan
belanja sendiri
Perlu bantuan untuk
mengantar belanja
Sama sekali tidak
mampu belanja
0
3Persiapan
makanan
Merencanakan, menyiapkan,
dan menghidangkan
makanan
Menyiapkan makanan
jika sudah disediakan
bahan makanan
Menyiapkan makanan
tetapi tidak mengatur
diet yang cukup
Perlu disiapkan dan
dilayani
0
4Perawatan
rumah
Merawat rumah sendiri atau
bantuan kadang-kadang
Mengerjakan pekerjaan
ringan sehari-hari (merapikan
tempat tidur, mencuci piring)
Perlu bantuan untuk
semua perawatan
rumah sehari-hari
Tidak berpartisipasi
dalam perawatan
rumah
0
5 Mencuci baju
Mencuci semua pakaian
sendiri
Mencuci pakaian yang kecil
Mencuci hanya
beberapa pakaian
Semua pakaian dicuci
oleh orang lain
0
6 Transport
Berpergian sendiri
menggunakan kendaraan
umum atau menyetir sendiri
Mengatur perjalanan sendiri
Perjalanan menggunakan
transportasi umum jika ada
yang menyertai
Perjalanan terbatas ke
taxi atau kendaraan
dengan bantuan orang
lain
Tidak melakukan
perjalanan sama sekali
0
7 Pengobatan
Meminum obat secara tepat
dosis dan waktu tanpa
bantuan
Tidak mampu
menyiapkan obat
sendiri
0
8 Manajemen
keuangan
Mengatur masalah finansial (
tagihan, pergi ke bank)
Mengatur pengeluaran
sehari-hari, tapi perlu
bantuan untuk ke bank untuk
Tidak mampu
mengambil keputusan
finansial atau
memegang uang
0
36

transaksi penting
TOTAL 0
Skor IADL
0 : Independen
1 : Kadang-kadang perlu bantuan
2 : Perlu bantuan sepanjang waktu
3 – 8 : Tidak beraktivitas / dikerjakan oleh orang lain
Total skor = 0 (Independen)
3.6 Penapisan Kognitif
AMT (Abreviated Mental Test)
a. Umur: 76 tahun
b. Waktu/jam sekarang: 15.00 WITA
c. Alamat tempat tinggal: Gianyar
d. Tahun ini: 2012
e. Saat ini berada di mana: Rumah Sakit
f. Mengenali orang lain di RS (dokter, perawat)
g. Tahun kemerdekaan RI: Tahun 45
h. Nama presiden RI: SBY
i. Tahun kelahiran pasien
j. Menghitung terbalik (20 s/d 1)
0.Salah 1.Benar
0.Salah 1.Benar
0.Salah 1.Benar
0.Salah 1.Benar
0.Salah 1.Benar
0.Salah 1.Benar
0.Salah 1.Benar
0.Salah 1.Benar
0.Salah 1.Benar
0.Salah 1.Benar
Skor AMT:
0 – 3 : Gangguan kognitif berat
4 – 7 : Gangguan kognitif sedang
8 – 10 : Normal
Total Skor:
8 : Normal
Perasaan hati (afeksi)
Baik Labil Depresi Agitasi Cemas
3.7 Penapisan Depresi
GDS (Geriatri Depression Scale)
No. Keterangan Ya Tidak
1 Apakah anda sebenarnya puas dengan kehidupan anda? 0 1
2Apakah anda telah meninggalkan banyak kegiatan dan minat atau
kesenangan anda? 1 0
37

3 Apakah anda merasa kehidupan anda kosong? 1 0
4 Apakah anda sering merasa bosan? 1 0
5 Apakah anda sangat berharap terhadap masa depan? 0 1
6Apakah anda merasa targanggu dengan pikiran bahwa anda tidak
dapat keluar dari pikiran anda? 1 0
7 Apakah anda merasa mempunyai semangat yang baik setiap saat? 0 1
8Apakah anda merasa takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi
pada diri anda? 1 0
9 Apakah anda merasa bahagia untuk sebagian besar hidup anda? 0 1
10 Apakah anda sering merasa tidak berdaya? 1 0
11 Apakah anda sering merasa resah dan gelisah? 1 0
12Apakah anda lebih senang berada di rumah daripada pergi ke luar
rumah dan melakukan hal-hal yang baru? 1 0
13 Apakah anda sering merasa khawatir terhadap masa depan anda? 1 0
14Apakah anda merasa memiliki banyak masalah dengan daya ingat
anda dibandingkan kebanyakan orang?1 0
15 Apakah menurut anda hidup anda saat ini menyenangkan? 0 1
16 Apakah anda sering merasa sedih? 1 0
17 Apakah saat ini anda merasa tidak berharga? 1 0
18 Apakah anda sangat mengkhawatirkan masa lalu anda? 1 0
19Apakah anda merasa hidup ini sangat menarik dan
menyenangkan? 0 1
20 Apakah sulit bagi anda untuk memulai sesuatu hal yang baru? 1 0
21 Apakah anda merasa penuh semangat? 0 1
22 Apakah anda merasa bahwa keadaan anda tidak ada harapan? 1 0
23Apakah anda merasa orang lain memiliki keadaan yang lebih baik
dari anda? 1 0
24 Apakah anda sering merasa sedih terhadap hal-hal kecil? 1 0
25 Apakah anda sering merasa ingin menangis ? 1 0
26 Apakah anda mempunyai masalah dalam berkonsentrasi? 1 0
38

27 Apakah anda merasa senang ketika bangun di pagi hari? 0 1
28Apakah anda lebih memilih untuk tidak mengikuti pertemuan-
pertemuan sosial atau masyarakat? 1 0
29 Apakah mudah bagi anda untuk membuat keputusan? 0 1
30 Apakah pikiran anda secerah biasanya? 0 1
TOTAL 2
Skor antara 0-9 : Normal
Skor antara 10-19 : Mild depression
Skor antara 20-30 : Severe depression
Total skor = 2 (Normal)
3.8 Penapisan Inkontinensia
Pertanyaan : Apakah anda mengompol atau BAB tanpa disadari ?
0 Tidak pernah
1,0Kadang-kadang kehilangan kontrol berkemih/ menggunakan alat bantu untuk berkemih &
BAB
2,5 Kehilangan kontrol berkemih sedikitnya sekali dalam sebulan
4,0Kehilangan kontrol berkemih sedikitnya 2 kali sebulan /kadang-kadang kehilangan
kontrol BAB
5,0 Kehilangan kontrol BAB sedikitnya sekali dalam sebulan
5,5 Kehilangan kontrol berkemih sedikitnya sekali dalam seminggu
6,5 Kehilangan kontrol BAB sedikitnya 2 kali sebulan
8,0Kehilangan kontrol BAB sedikitnya sekali seminggu/kehilangan kontrol berkemih
sedikitnya sekali tiap hari
10 Kehilangan kontrol BAB sedikitnya sekali sehari
10,5 Tidak bisa mengontrol fungsi berkemih sama sekali
11,5 Tidak bisa mengontrol BAB sama sekali
Inkontinensia dikelompokkan menjadi :
0 : Tidak ada inkontinensia
1-2,5 : Inkontinensia ringan
4,0-6,5 : Inkontinensia sedang
≥ 8 : Inkontinensia berat
Total skor = 0 (Tidak ada inkontinensia)
39

3.9 Penapisan Nutrisi Mini (Mini Nutritional Assessment)
No. Penilaian Nilai
1 Indeks masa tubuh : BB/TB (m2)
a. < 19 = 0
b. 19-21= 1
c. 21-23 = 2
d. >23 = 3
0
2 Lingkar lengan atas (cm)
a. < 21 = 0
b. 21-22 = 0.5
c. >22 = 1
0
3 Lingkar betis (cm)
a. ≤ 31 = 0
b. >31 = 1
0
4 BB selama 3 bulan terakhir :
a. Kehilangan > 3kg = 0
b. Tidak tahu = 1
c. Kehilangan antara 1-3 kg = 2
d. Tidak kehilangan BB = 3
1
5 Hidup tidak tergantung (tidak di tempat perawatan atau RS) :
Tidak = 1 / Ya = 01
6 Menggunakan lebih dari 3 obat perhari
Tidak = 1 / Ya = 00
7 Mengalami stres psikologis atau penyakit akut dalam 3 bln terakhir :
Tidak = 1 / Ya = 01
8 Mobilitas
a. Hanya terbaring atau di atas kursi roda = 0
b. Dapat bangkit dari tempat tidur tapi tidak keluar rumah = 1
c. Dapat pergi keluar rumah = 2
2
9 Masalah neuropsikologis
a. Demensia berat dan depresi = 0
b. Demensia ringan =1
c. Tidak ada masalah psikologis = 2
2
10 Nyeri tekan atau luka kulit
Tidak = 1 / Ya = 01
40

11 Berapa banyak daging yang dikonsumsi setiap hari ?
a. 1 x makan = 0
b. 2 x makan = 1
c. 3 x makan = 2
1
12 Asupan protein terpilih
a. Minimal 1x penyajian poduk-produk susu olahan (susu, keju, yoghurt, es krim)
perhari.
Ya = 1 / Tidak = 0
b. Dua atau lebih penyajian produk kacang-kacangan (tahu, tempe, susu kedelai )
dan telur perminggu
Ya = 1 / Tidak = 0
c. Daging, ikan, unggas tiap hari
Ya = 1 / Tidak = 0
2
13 Konsumsi 2 atau lebih penyajian sayur atau buah-buahan per hari
Ya = 1 / Tidak = 00
14 Bagaimana asupan makanan 3 bulan terakhir
a. Kehilangan nafsu makan berat = 0
b. Kehilangan nafsu makan sedang = 1
c. Tidak kehilangan nafsu makan = 2
2
15 Berapa banyak cairan (air, jus, kopi, teh, susu) yang dikonsumsi per hari.
a. < 3 cangkir = 0
b. 3 - 5 cangkir = 0,5
c. > 5 cangkir = 1
0
16 Pola makan
a. Tidak dapat makan tanpa bantuan = 0
b. Dapat makan sendiri dengan sedikit kesulitan = 1
c. Dapat makan sendiri tanpa masalah = 2
2
17 Apakah mereka tahu bahwa mereka memiliki masalah gizi ?
a. Malnutrisi = 0
b. Tidak tahu atau malnutrisi sedang = 1
c. Tidak ada masalah gizi = 2
2
18 Dibandingkan dengan orang lain dengan usia yang sama, bagaimana mereka menilai
kesehatan mereka sekarang ?
Tidak baik = 0, Tidak tahu = 0.5, Baik = 1, Lebih baik = 2
1
TOTAL 19
Interpretasi:
41

Skor > 24 : Gizi baik
Skor 17-23,5 : Berisiko malnutrisi
Skor < 17 : Malnutrisi
Total Skor = 19 (Berisiko malnutrisi)
3.10 Assesmen Lingkungan, Keamanan, Bahaya/Penyebab Jatuh
Lingkungan
1. Apakah tersedia kamar khusus penderita : Ya
2. Kamar tidur : Sendiri
3. Kamar mandi : Sendiri
4. WC : Sendiri
5. Dapur : Sendiri
6. Kamar duduk : Sendiri
7. Jumlah ruang yang ada di rumah penderita : 2 ruangan
8. Apakah rumah mempunyai tangga : Tidak
9. Apakah lingkungan rumah cukup nyaman : Ya
10. Kebersihan rumah : Cukup
11. Apakah rumah berventilasi : Ya
12. Apakah terdapat tanda-tanda kurang urus (neglect) : Tidak
13. Makanan basi di almari : Tidak
14. Alat makan yang tidak dicuci : Tidak
15. Tumpukan pakaian kotor : Ya
16. Sampah berserakan : Tidak
Keamanan
17. Apakah penderita dapat:
a. Membuka / mengunci pintu : Ya
b. Mencapai sakelar lampu : Ya
c. Mencari pertolongan bila perlu : Ya
d. Berjalan di dalam rumah dengan aman : Ya
18. Apakah terdapat bahaya yang jelas / nyata
a. Fitting lampu yang bertumpuk : Tidak
42

b. Kabel-kabel listrik yang telanjang : Tidak
c. Penyinaran yang tidak terang (siang/malam) : Ya
d. Perabotan (besar/kecil) yang berserakan : Tidak
e. Perabotan/mebel yang tidak aman
(mudah patah/ringkih, mudah terguling dan sebagainya) : Tidak
f. Karpet, keset atau lantai yang tidak rata : Tidak
Bahaya / penyebab jatuh
19. Lingkungan rumah:
a. Lantai dan karpet dalam keadaan baik dan tidak menonjol
sana-sini, yang mungkin menyebabkan terpeleset/jatuh : Tidak
b. Pencahayaan cukup terang dan tidak silau : Ya
c. Penempatan lampu cukup baik, terutama di dekat tangga
dan antara tempat tidur dan kamar mandi : Ya
d. Sakelar lampu di tempat beresiko tinggi kalau perlu dari jenis
yang bisa berpendar : Tidak
e. Telepon ditempatkan sedemikian sehingga tidak perlu bergegas
untuk menjawab panggilan : Tidak
f. Kabel-kabel listik tidak terletak di lantai : Ya
g. Bila perlu harus diperpendek dan dipakukan ke dinding : Tidak
h. Tak terdapat barang berserakan di jalan tempat lampu : Ya
20. Kamar mandi:
a. Terdapat ril pegangan di daerah toilet dan bak mandi dan
mudah didapat bila diperlukan : Tidak
b. Permukaan lantai pancuran atau bak rendam tidak licin : Ya
c. Bila mempergunakan pelapis bak rendam harus dari kualitas
baik : Tidak
d. Belakang keset harus berlapis karet yang tidak bisa licin : Ya
e. Drainase air harus baik hingga mencegah lantai licin : Ya
21. Kamar tidur:
a. Keset tidak merupakan hambatan yang memungkinkan terpeleset
atau tergelincir, terutama yang di jalan lalu ke kamar mandi : Ya
43

b. Terdapat meja di samping tempat tidur untuk meletakkan
kacamata atau barang lain, sehingga tidak diletakkan di lantai
di samping tempat tidur : Tidak
22. Dapur
a. Lantai terbuat dari bahan yang tidak licin : Ya
b. Tumpahan-tumpahan cepat dibersihkan untuk
mencegah terpeleset : Ya
c. Bahan untuk membersihkan dan memasak diletakkan di tempat
yang terjangkau : Ya
d. Disediakan kursi tinggi untuk keperluan mencuci piring : Tidak
e. Tersedia tempat pijakan yang stabil untuk mencapai barang
yang letaknya agak tinggi : Tidak
23. Kamar duduk:
a. Keset-keset tidak terletak di atas karpet atau terserak
di sana-sini : Ya
b. Mebel/perabotan diletakkan sedemikian rupa sehingga jalan
cukup lebar : Ya
c. Tinggi kursi dan sofa cukup sehingga mudah bagi lansia untuk
duduk atau bangkit darinya : Ya
24. Tangga : -
25. Di luar rumah
a. Pintu masuk depan dan belakang dalam keadaan baik : Ya
b. Jalan lalu harus bebas dari lumpur atau air atau air di musim
hujan sehingga mencegah terpeleset/jatuh : Ya
c. Anak tangga / ril pegangan harus terpasang kuat / baik : Ya
3.11 Daftar Masalah
Dari data-data yang dikumpulkan, didapatkan bahwa penderita memiliki
masalah sebagai berikut:
Intrinsik:
ADL Barthel : Mandiri
44

IADL : Mandiri
AMT : Normal
GDS : Normal
Inkontinensia : Tidak ada inkontinensia
MNA : Berisiko malnutrisi
Ekstrinsik :
1. Lingkungan rumah:
a. Penyinaran yang tidak terang (siang/malam).
b. Karpet, keset atau lantai yang tidak rata.
2. Kamar mandi:
a. Tidak terdapat ril pegangan di daerah toilet dan bak mandi.
b. Permukaan lantai pancuran atau bak rendam licin.
3. Kamar tidur:
a. Tidak terdapat meja di samping tempat tidur untuk meletakkan kacamata
atau barang lain, sehingga tidak diletakkan di lantai di samping tempat tidur.
4. Dapur:
a. Tidak tersedia kursi tinggi untuk keperluan mencuci piring.
b. Tidak tersedia tempat pijakan yang stabil untuk mencapai barang yang
letaknya agak tinggi.
3.12 Pemeriksaan Fisik (tanggal 14 September 2012)
Status Present
a. Kesadaran : E4V5M6
b. Tekanan darah/nadi
Berbaring : 140/90 mmHg Nadi : 88 kali/menit
45

Duduk : 150/90 mmHg Nadi : 90 kali/menit
Berdiri : Tidak dilakukan Nadi : Tidak dilakukan
c. Laju respirasi : 24 kali/menit
d. Suhu aksila : 37,5°C
e. Antropometri
Berat badan : 50 kg
Tinggi badan : 163 cm
BMI : 18,82 kg/m2
Tinggi lutut : 45 cm
Lingkar lengan atas : 19,7 cm (kanan dan kiri)
Kesimpulan : Gizi baik
Status General
Mata : anemis -/- , ikterus -/- , refleks pupil +/+ isokor,
oedem palpebra (-/-)
THT
Telinga : bentuk normal, tanda-tanda radang (-), bekas luka (-)
Hidung : bentuk normal, tanda-tanda radang (-), ekskoriasi (-)
bekuan-bekuan darah (-)
Tenggorokan : pembesaran tonsil (-), hiperemis (-), faring hiperemis (-)
Lidah : atrofi papil lidah (-)
Leher : JV PR + 0 cm H2O, pembesaran kelenjar getah bening (-)
Thorax : simetris (+), retraksi (-)
Jantung
Inspeksi : tidak tampak pulsasi iktus kordis
Palpasi : iktus kordis teraba pada ICS V MCL S, kuat angkat (-)
Perkusi : batas atas jantung ICS II kiri
batas kanan jantung PSL kanan
batas kiri jantung MCL kiri ICS V
Auskultasi : S1S2 tunggal, regular, murmur (-)
Paru
Inspeksi : simetris saat statis dan dinamis
46

Palpasi : vocal fremitus N N
N N
↑ ↑
Perkusi : sonor sonor
sonor sonor
redup redup
Auskultasi : vesikuler + + ronkhi - - wheezing - -+ + - - - -+ + + + - -
Abdomen
Inspeksi : distensi (-), meteorismus (-), denyut epigastrial (-)
Auskultasi : bising usus (+) normal
Palpasi : nyeri tekan (-)
hepar / lien tidak teraba, balotement (-/-),
nyeri ketok CVA (-/-)
Perkusi : timpani (+), ascites (-)
Ekstremitas
akral hangat + + edema - -
+ + - -
47

3.13 Pemeriksaan Penunjang
Darah Lengkap (11 September 2012)
Pemeriksaan Hasil Satuan Normal Remarks
WBC 9,30 103µL 4,10 - 11,00
% Neutrofil 81,10 % 47,00 - 80,00
% Limfosit 9,70 % 13,00 - 40,00
% Monosit 4,50 % 2,00 - 11,00
% Eosinofil 4,32 % 0,00 - 5,00
% Basofil 0,37 % 0,00 - 2,00
#Neutrofil 7,54 103µL 2,50 - 7,50
#Limfosit 0,90 103µL 1,00 - 4,00
#Monosit 0,42 103µL 0,10 - 1,20
#Eosinofil 0,40 103µL 0,00 - 0,50
#Basofil 0,00 103µL 0,00 - 0,10
RBC 4,17 106µL 4,50 - 5,90
Hemoglobin 11,30 g/dL 13,50 - 17,50
Hematokrit 36,70 % 41,00 - 53,00
Platelet 368,10 103µL 150,00 - 440,00
MCV 88,00 fL 80,00 - 100,00
MCH 27,10 Pg 26,00 - 34,00
MCHC 30,70 g/dL 31,00 - 36,00
Kimia Darah (11 September 2012)Pemeriksaan Hasil Satuan Nilai Normal Remarks
SGOT 8,80 U/L 11,00 – 27,00 Rendah
SGPT 18,60 U/L 11,00 – 34,00
BUN 13,00 mg/dL 8,00 – 23,00
Kreatinin 0,98 mg/dL 0,50 - 0,90 Tinggi
Albumin 2,93 g/dL 3,40 - 4,80 Rendah
Kolesterol 155,00 mg/dL <200
HDL Direk 52,00 mg/dL 40,00 - 65,00
LDL Kolesterol direk 90,00 mg/dL <100
Trigliserida 65,00 mg/dL <150
Glukosa darah sewaktu 75,00 mg/dL 70,00 - 140,00
48

Analisis Gas Darah (13 September 2012)Pemeriksaan Hasil Satuan Nilai Normal Remarks
pH 7,43 - 7,35 - 7,45
pCO2 51,00 mmHg 35,00 - 45,00 Tinggi
pO2 86,00 mmHg 80,00 - 100,00
HCO3- 33,90 mmol/L 22,00 - 26,00 Tinggi
TCO2 35,50 mmol/L 24,00 - 30,00 Tinggi
Beecf 9,60 mmol/L -2,00 - 2,00 Tinggi
SO2c 97,00 % 95% - 100%
Natrium 137,00 mmol/L 136,00-145,00
Kalium 4,30 mmol/L 3,5-5,10
EKG
- Irama : Sinus
- Heart rate : 88 kali per menit, reguler
- Axis : Normal
- ST-T Change : Negatif
- QRS Complex : Normal
- Kesan : Sinus Rhythm
Foto Thorax AP
49

Besar dan bentuk jantung normal.
Tampak infiltrat di suprahiler-paracardial kanan dan paracardial kiri.
Sinus pleura kanan dan kiri tajam.
Diafragma kanan dan kiri normal.
Tulang-tulang tidak tampak kelainan.
Kesan: Pneumonia
3.14 Diagnosis
Acute confusional state (perbaikan) ec suspek meningitis bakteri dd TB
Pneumonia (PK) PSI Class III
Suspek TB paru
Hipertensi stage 1 (dalam pengobatan)
3.15 Impairment
Imobilisasi
Gangguan pendengaran
Gangguan penglihatan
50

3.16 Dissabillity
Tidak ada akibat objektif pada kemampuan fungsional dari organ atau pada
pasien.
3.17 Handicap
Tidak ada hambatan untuk melakukan aktivitas sosial baik di rumah
maupun di lingkungan sosialnya.
3.18 Penatalaksanaan
a. Terapi
- O2 nasal kanul 2 liter per menit
- IVFD NaCl 0,9% ~ 20 tetes per menit
- Ceftriaxone 2 x 2 gr i.v
- Azythromycin 1 x 500 mg i.v
- Ambroxol 3 x CI p.o
- Captopril 2 x 25 mg p.o
- Diet tinggi kalori, tinggi protein
b. Rencana diagnostik
- Sputum gram/CC/ST jika ada bahan
- BTA sputum 3 kali
- Foto thoraks 7 hari lagi
c. Monitoring
- Tanda vital
- Keluhan
3.19 Prognosis
Ad vitam : dubius ad bonam
Ad fungsionam : dubius ad bonam
51

BAB IVKESIMPULAN
Diagnosis dapat ditegakkan melalui riwayat keluhan melalui anamnesis
dan identifikasi faktor risiko, dilanjutkan pemeriksaan fisik untuk identifikasi
tanda dan gejala, serta melakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan
kecurigaan pada pemeriksaan tanda dan gejala pada pasien.
Manifestasi klinis pneumonia komunitas pada geriatri memiliki rentang
yang luas, mulai dari hanya takipnea dan takikardia saja, sampai perubahan
kesadaran yang tampak menakutkan bagi sebagian besar orang dan bisa
menimbulkan kepanikan. Umumnya, gejala-gejala khas pneumonia hanya ringan
atau malah tidak terlihat, misalnya demam, batuk-batuk produktif, atau sesak
napas. Pasien bisa datang dengan keluhan lesu, lemas, atau penurunan nafsu
makan. Pada kebanyakan kasus, timbul perubahan kesadaran atau delirium (acute
confusional state). Gejala ini memang spesifik hanya ditemukan pada lanjut usia,
dan tidak ditemukan pada kelompok usia yang lebih muda.
Pada kasus ini, pasien mengeluh batuk-batuk. Batuk dikatakan sudah
muncul sejak 1 bulan sebelum masuk rumah sakit, namun dirasakan bertambah
berat saat hari ke-3 dirawat di RSUP Sanglah. Batuk dirasakan pasien terus-
menerus sepanjang hari, kadang-kadang disertai dahak kental berwarna putih
tanpa darah. Pasien juga mengeluh sesak napas dan demam, tapi saat pemeriksaan
sudah mulai berkurag.
Berdasarkan pemeriksaan fisik yang ditemukan pada pasien, didapatkan
temuan bahwa pasien dalam kesadaran yang baik dengan gizi yang tergolong baik
berdasarkan nilai BMI pasien 18,82. Tekanan darah adalah 150/90 mmHg dan
nadi dan suhu aksila dalam batas normal. Pasien juga tidak mengeluhkan nyeri.
Laju napas pasien meningkat menjadi 24 kali, dimana rentang normal laju napas
berkisar antara 16-20 kali sehingga pasien dapat dikatakan mengalami takipnea.
Peningkatan laju napas pada pasien ini diakibatkan oleh tingginya kadar CO2.
Karbondioksida ini dapat secara bebas berdifusi melalui sawar darah otak.
Peningkatan kadar karbondioksida dalam otak dapat meningkatkan kadar ion
52

hidrogen sehingga dapat menstimulasi kemoreseptor sentral, kemudian akan
meningkatkan ventilasi.
Pemeriksaan fisik pada pasien ini didapatkan jantung berada dalam batas
normal. Hal ini menggambarkan bahwa pada pasien ini belum ditemukan adanya
komplikasi pada jantungnya. Pada palpasi paru, teraba getaran yang meningkat
pada bagian inferiornya dan pada auskultasi paru terdengar suara napas tambahan
yaitu, ronki pada bagian inferior paru.
Pada pemeriksaan abdomen dan ekstremitas masih berada dalam batas
normal. Ekstremitas masih hangat dan tidak ditemukan tanda-tanda sianosis yang
menggambarkan perfusi jaringan ke tubuh bagian perifer masih berlangsung
dengan baik.
Pada kasus ini dijumpai adanya peningkatan kadar HCO3- dan base excess
untuk mempertahankan pH tetap berada dalam rentang normal, sehingga pada
pasien ini tidak mengalami asidosis respiratorik.
Pada foto thoraks ditemukan adanya gambaran infiltrat di suprahiler kanan
serta paracardial kanan dan kiri, dimana hal tersebut dapat menunjukkan bahwa
penderita mengalami pneumonia.
Dari gambaran EKG, pada kasus ini tidak ditemukan adanya gambaran P
pulmonal dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda gambaran hipertropi ventrikel
kanan (axis normal dan R/S di V1 < 1, R/S di V6 > 1), sehingga kemungkinan
pada pasien ini belum terjadi adanya komplikasi ke arah cor pulmonale.
Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan perubahan kesadaran, demam,
batuk-batuk, tubuh lemas, imobilisasi, dan ronki pada seluruh lapangan paru.
Namun, sekali lagi, semuanya dapat tidak khas pada pasien-pasien geriatri atau
malah memberikan gejala yang sama sekali tak terduga. Dengan demikian,
dibutuhkan pemeriksaan penunjang berupa laboratorium, foto thoraks, dan kultur
darah.
Identifikasi faktor risiko merupakan langkah penting dalam pencegahan
dan penatalaksanaan pneumonia. Meskipun saat ini pemahaman faktor risiko
pneumonia dalam banyak hal masih belum lengkap, diperlukan pemahaman
53

interaksi dan hubungan antara faktor-faktor risiko sehingga memerlukan
investigasi lebih lanjut. Faktor risiko timbulnya pneumonia antara lain:
h. Usia > 65 tahun.
i. Penyakit kronik (misalnya ginjal dan paru).
j. Mempunyai riwayat diabetes mellitus.
k. Imunosupresi (misalnya karena obat-obatan atau HIV).
l. Ketergantungan alkohol.
m. Penyakit virus yang baru terjadi (misalnya influenza).
n. Malnutrisi
Pada pasien ini didapatkan faktor risiko berupa usia pasien yang sudah di atas 65
tahun (usia pasien 76 tahun) dan pasien memiliki risiko malnutrisi.
Keluhan pasien muncul pada hari ke-3 saat dirawat di rumah sakit, dimana
sesuai dengan definisi pneumonia komunitas (PK) yaitu infeksi yang terjadi dalam
48 jam setelah dirawat di rumah sakit selama kurang dari 14 hari. Berdasarkan
petunjuk dari Therapeutic Guidelines: Antibiotic (Guidelines) untuk
menggunakan Pneumonia Severity Index (PSI) dalam mengarahkan tempat
perawatan pasien dan pemilihan antibiotika, pada pasien ini didapatkan skor 86
dan dimasukkan ke dalam PK (CAP) PSI kelas III.
Kalkulasi Pneumonia Severity Index (PSI)
Karakteristik Poin
Faktor demografi
Umur
Laki-laki
Perempuan
Rumah perawatan
Penyakit penyerta
Penyakit neoplastik
Penyakit liver
Gagal jantung kongestif
Penyakit serebrovaskular
Penyakit ginjal kronik
Umur (tahun)
Umur (76–10)
+10
+30
+20
+10
+10
+10
54

Pemeriksaan fisik
Perubahan metal status akut
Lajun pernapasan ≥ 30/menit
Tekanan darah sistolik < 90 mmHg
Temperatur < 35 atau ≥ 40°C
Nadi ≥ 125/menit
Pemeriksaan laboratorium dan radiografi
pH arterial < 7,35
BUN ≥ 30 mg/dl (11 mmol/l)
Natrium < 130 mmol/l
Glukosa ≥ 250 mg/dl (14 mmol/l)
Hematokrit < 30%
PaO2 < 60 mmHg atau saturasi O2 < 90%
Efusi pleura
+20
+20
+20
+15
+10
+30
+20
+20
+10
+10
+10
+10
Total 86
*) Penilaian untuk tingkat keparahan pneumonia kelas II-V: kelas II, 1-70; kelas
III, 71-90; kelas IV, 91-130; kelas V >130.
Penatalaksanaan PK pada pasien geriatri dibagi menjadi dua, yaitu terapi
definitif dan terapi suportif. Terapi definitif diarahkan pada pemberian antibiotik
yang tepat untuk pasien. Bagian ini sama dengan terapi antibiotik pada pasien
golongan usia yang lebih muda. Antibiotik idealnya diberikan sesuai dengan uji
kultur resistansi sputum. Namun, untuk menyelamatkan nyawa pasien dan
mencegah perburukan klinis, diberikan antibiotik empiris berdasarkan pola kuman
yang paling sering muncul pada pasien-pasien lanjut usia (dalam hal ini S.
pneumonia). Perbedaan lebih mencolok pada terapi suportif di mana pada pasien
geriatri, terdapat banyak permasalahan geriatri yang harus ditangani baik dengan
medikamentosa, maupun terapi fisik dan rehabilitasi (fisioterapi), misalnya untuk
imobilisasi, instabilitas dan riwayat jatuh, malnutrisi, insomnia, dan gangguan
pendengaran dan penglihatan.
Pemilihan antibiotik pada pasien PK geriatri sudah didokumentasikan
dalam banyak literatur. Salah satu rekomendasi yang paling banyak dipakai adalah
55

yang berasal dari American Thoracic Society (ATS) dan Infectious Diseases
Society of America (IDSA) yang menyebutkan bahwa antibiotik empiris diarahkan
tiga kemungkinan etiologi tersering pada pneumonia komunitas, yaitu S.
pneumonia, Legionella pneumophylla, dan Chlamydia pneumoniae. Pasien
dengan PK oleh untuk pasien yang memerlukan perawatan di rumah sakit dengan
penyakit kardiopulmoner dengan atau tanpa faktor modifikasi, terapi yang
dianjurkan adalah terapi dengan golongan β-lactam (cefotaxim, ceftriaxone,
ampicillin/sulbactam, dosis tinggi ampicillin intravena) yang dikombinasi dengan
makrolide atau doksisiklin oral atau intravena, atau pemberian fluroquinolon
antipneumococcal intravena saja. Pasien ini diberikan terapi berupa β-lactam
(ceftriaxone) yang dikombinasi dengan makrolide (azythromycin). Pemberian
antibiotika diberikan selama 7-14 hari. Selain itu, pasien memperoleh terapi
suportif berupa oksigenasi untuk sesaknya dan terapi simtomatis berupa ambroxol
untuk keluhan batuk pasien. Pasien juga dianjurkan untuk diet tinggi kalori dan
tinggi protein untuk menunjang nutrisi agar gizi pasien tetap dalam keadaan baik.
Pemberian antibiotik umumnya dilakukan 7-14 hari, tergantung jenis
antibiotiknya. Evaluasi pengobatan antibiotik dilakukan dengan beberapa cara,
yaitu klinis, laboratorium (penurunan leukosit dan hitung jenis), dan foto toraks
ulang. Penyembuhan pneumonia komunitas biasanya diikuti dengan perbaikan
status fungsional dan nutrisi. Pasien dirawat jalan dan diminta untuk kontrol
setelah kondisi pulih dan status fungsional meningkat.
Prognosis pada pasien ini adalah mengarah ke baik (dubius ad bonam)
karena keluhan sesak dan batuknya sudah berkurang setelah pemberian terapi.
Selain itu, dari penapisan status fungsional dan kognitif, pasien yang sudah lanjut
usia masih bisa mandiri dan tidak ada masalah. Meskipun pasien mengalami
gangguan pendengaran dan penglihatan, namun hal tersebut tidak terlalu
mengganggu pasien untuk bersosialisasi dengan lingkungannya.
Pasien yang mengalami hipertensi mungkin saja tampak sehat atau
memiliki faktor-faktor risiko kardiovaskular seperti:
1. Usia (≥ 55 tahun untuk pria dan 65 tahun untuk wanita).
2. Diabetes mellitus
56

3. Dislipidemia (peningkatan kolesterol low-density lipoprotein (LDL), kolesterol
atau trigliserida total, dan rendah kolesterol high-density lipoprotein (HDL)).
4. Mikroalbuminuria
5. Riwayat keluarga yang mengalami penyakit kardiovaskuler di usia muda.
6. Obesitas (BMI ≥ 30 kg/m2).
7. Kurangnya aktivitas fisik.
8. Merokok
Pada kasus ini pasien termasuk dalam kelompok lanjut usia, dengan kurangnya
aktivitas yang dilakukan selama beberapa tahun belakangan ini, dan pola makan
pasien yang tidak terkontrol.
Untuk mendiagnosis hipertensi, pengukuran tekanan darah harus dilakukan
dalam keadaan duduk rileks atau berbaring selama 5 menit. Apabila hasil
pengukuran menunjukkan angka 140/90 mmHg atau lebih, hal ini dapat diartikan
sebagai keberadaan hipertensi, tetapi diagnosis tidak dapat dipastikan hanya
berdasarkan satu kali pengukuran saja. Jika pada pengukuran pertama hasilnya
tinggi, maka tekanan darah diukur kembali sebanyak 2 kali pada 2 hari berikutnya
untuk meyakinkan adanya hipertensi. Pada dasarnya dugaan kuat seseorang
menderita hipertensi terjadi apabila terdapat hal-hal berikut:
1. Riwayat hipertensi dalam keluarga
2. Usia penderita
3. Data faktor risiko
Pada pasien ini, tekanan darahnya diukur 2 kali, yaitu saat pasien
berbaring dan duduk. Tekanan darah saat pasien berbaring adalah 140/90 mmHg
dan pada posisi duduk tekanan darahnya adalah 150/90 mmHg. Sesuai dengan
klasifkasi hipertensi menurut The Seventh Report of The Joint National Commitee
on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure
(JNC-VII), pasien termasuk ke dalam klasifikasi hipertensi stage 1.
Faktor risiko hipertensi antara lain faktor genetika, ras, usia > 50 tahun,
jenis kelamin, stres psikis, obesitas, asupan garam berlebih, merokok,
dan konsumsi alkohol. Pada pasien ini didapatkan faktor risiko berupa usia yang
sudah di atas 50 tahun (usia pasien 76 tahun), dimana berdasarkan epidemiologi
57

lanjut usia memang cenderung menderita hipertensi. Faktor kelamin juga dapat
berpengaruh, dimana wanita premenopause cenderung memiliki tekanan darah
yang lebih tinggi daripada pria pada usia yang sama, meskipun perbedaan di
antara jenis kelamin kurang tampak setelah usia 50 tahun. Penyebabnya, sebelum
menopause, wanita relatif terlindungi dari penyakit jantung oleh hormon estrogen.
Kadar estrogen menurun setelah menopause dan wanita mulai menyamai pria
dalam hal penyakit jantung.
Dari riwayat keluarga, anak pasien juga tidak terdiagnosis hipertensi,
namun dari generasi sebelumnya tidak diketahui apakah ada yang mengalami
hipertensi atau tidak.
Penatalaksanaan hipertensi terdiri dari terapi non-farmakologis dan
farmakologis. Terapi non-farmakologis bertujuan mengendalikan faktor-faktor
risiko serta penyakit penyerta lainnya. Terapi non-farmakologis adalah dengan
modifikasi gaya hidup pasien, antara lain:
e. Menurunkan berat badan sampai batas ideal pada pasien hipertensi yang
mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.
f. Mengubah pola makan, yaitu mengurangi asupan garam sampai kurang dari 3
gram natrium (disertai dengan asupan kalsium, magnesium, dan kalium yang
cukup), meningkatkan asupan buah dan sayur, dan mengurangi asupan lemak,
serta mengurangi konsumsi alkohol.
g. Olah raga teratur yang tidak terlalu berat. Pasien hipertensi primer tidak perlu
membatasi aktivitasnya selama tekanan darahnya terkendali.
h. Berhenti merokok karena merokok dapat merusak jantung dan sirkulasi darah
dan meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke.
Untuk terapi farmakologis, berdasarkan JNC-VII antara lain:
f. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACE-inhibitor) menyebabkan
penurunan tekanan darah dengan cara melebarkan arteri.
g. Angiotensin II Receptor Blocker (ARB) menyebabkan penurunan tekanan
darah dengan suatu mekanisme yang mirip dengan ACE-inhibitor.
58

h. Beta Blocker yang menghambat efek sistem saraf simpatis. Sistem saraf
simpatis adalah sistem saraf yang dengan segera akan memberikan respon
terhadap stres, dengan cara meningkatkan tekanan darah.
i. Calsium Channel Blocker (CCB) atau Calsium antagonist menyebabkan
melebarnya pembuluh darah dengan mekanisme yang benar-benar berbeda.
j. Diuretik, terutama golongan Thiazide atau Aldosterone antagonist. Diuretik
membantu ginjal membuang garam dan air yang akan mengurangi volume
cairan di seluruh tubuh sehingga menurunkan tekanan darah. Diuretik juga
menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Diuretik akan menyebabkan
hilangnya kalium melalui air, sehingga harus diberikan tambahan kalium atau
obat penahan kalium.
59

DAFTAR PUSTAKA
1. Vidal CG, Fernandez NS, Carratala J, Diaz V, Verdaguer R, Dorca J, Manresa F, dan Gudiol F. Early mortality in patients with communityacquired pneumonia: causes and risk factors. Eur Respir J 2008; 32: 733-739.
2. Situmorang AT. 2012. Hubungan Kadar Procalcitonin saat Awal Masuk pada Pasien dengan Pneumonia Komunitas terhadap Skor CURB-65. Tesis. Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan.
3. Sajinadiyasa GK, Rai IB, Sriyeni LG. Perbandingan antara Pemberian Antibiotika Monoterapi dengan Dualterapi terhadap Outcome pada Pasien Community Acquired Pneumonia (CAP) di Rumah Sakit Sanglah Denpasar. J Peny Dalam 2011; 12: 13-20.
4. Niederman MS, Mandel LA, Anzueto A, Bass JB, Broughton WA, Campbell GD, Dean N, File T, Fine MJ, Gross PA et al. VICTOR L. YU, M.D. Guidelines for the Management of Adults with Community-acquired Pneumonia – Diagnosis, Assessment of Severity, Antimicrobial Therapy, and Prevention. Am J Respir Crit Care Med 2001; 163: 1730-1754.
5. Shah PB, Gludice JC, Griesback R, Morley TF, Vasoya A. The newer guidelines for the management of community-acquired pneumonia. JAOA 2004;104(12):5510-26.
6. Summary Executive. Pola Penyakit Penyebab Kematian di Indonesia. Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT). 2001: 2.
7. Dahlan Z. Pneumonia. Dalam: Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Sudoyo AW, Setiyohadi B, Alwi S, Simadibrata M, Setiati S (editor). 2007. Jakarta: Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam Universitas Indonesia.
8. Kuswardhani T. Penatalaksanaan Hipertensi pada Lanjut Usia. J Peny Dalam 2006; 136: 135-140.
9. Suhardjono. Hipertensi pada Usia Lanjut. Dalam: Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Sudoyo AW, Setiyohadi B, Alwi S, Simadibrata M, Setiati S (editor). 2007. Jakarta: Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam Universitas Indonesia.
10. Yogiantoro M. Hipertensi Esensial. Dalam: Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Sudoyo AW, Setiyohadi B, Alwi S, Simadibrata M, Setiati S (editor). 2007. Jakarta: Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam Universitas Indonesia.

11. Kurnia R. 2007. Karakteristik Penderita Hipertensi yang Dirawat Inap di Bagian Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Kota Padang Panjang Sumatera Barat Tahun 2002-2006. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan.
12. The Seventh Report of the Joint National Committee on prevention, detection, evaluation, and treatment of high blood pressure. NIH Publication No. 03-5233 December 2003.
13. Mcintosh KA, Maxwell DJ, Pulver LK, Horn F, Robertson MB, Kaye KI, Peterson GM, Dollman WB, Angelawai, dan Tett SE. A Quality Improvement Initiative to improve adherence to national guidelines for empiric management of community-acquired pneumonia in emergency departments. International Journal for Quality in Health Care 2011; 23: 142-150.
14. Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, Hanusa BH, Weissfeld LA, Singer DE, Coley CE, Marrie TJ, dan Kapoor WN. A Prediction Rule to Identify Low-Risk Patients with Community-Acquired Pneumonia. N Engl J Med 1997; 336: 243-250.