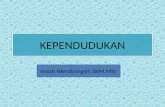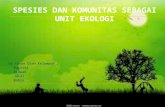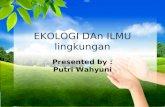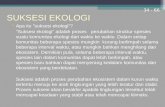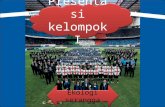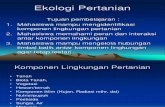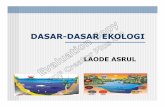Paradigma Ekologi Politik (Kel. 1)
-
Upload
bagus-priyambada -
Category
Documents
-
view
16 -
download
1
description
Transcript of Paradigma Ekologi Politik (Kel. 1)
PAPER
PARADIGMA EKOLOGI POLITIK
Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Politik Lingkungan dan SDA
PENDAHULUANBerawal dari banyaknya studi tentang perubahan iklim dan kebencanaan yang lebih berfokus pada persoalan yang muncul setelah bencana seperti yang berkaitan dengan proyek-proyek rehabilitas, pemulihan pasca bencana dan tata kelola bantuan. Padahal terdapat aspek lain yang tidak kalah penting yang belum banyak mendapat sorotan dari dunia akademis, yaitu tentang latar historis dan aspek multiskala yang membentuk kerentanan terhadap bencana dan dampaknya bagi masyarakat. Bencana selalu diidentikkan dengan sesuatu yang disebabkan oleh faktor alamiah dan seringkali mengabaikan unsur manusia ataupun alasan struktural (aspek endapan kejadian di masa lalu). Selain itu, kajian mengenai bencana juga kerap dijauhkan dari aspek politis dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang ada. Hal tersebut menyebabkan perubahan kondisi sosial dan ekologis di masyarakat yang pada gilirannya mengakibatkan kerentanan terhadap bencana.
Pendekatan ekologi politik menawarkan cara pandang berbeda dalam menyoroti bencana dan perubahan iklim dengan memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai relasi antara sistem (struktur) sosial dan kondisi ekologis agar nantinya dapat diketahui faktor yang membentuk, upaya pencegahan sekaligus cara mengurangi ancaman dan kerentanan terhadap resiko bencana akibat perubahan iklim. Melalui pendekatan ekologi politik dapat memberikan pemahaman tentang hubungan antara manusia dan alam dengan cara menganalisis bangunan sosial yang membentuk akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam. Mengingat, saat membicarakan mengenai akses dan kontrol maka akan menyangkut tentang distribusi kekuasaan. Sedangkan distribusi kekuasaan itu sendiri kerap tidak imbang sehingga menyebabkan konflik. Konflik tersebut yang berperan dalam membentuk konsekuensi dan kecenderungan perubahan lingkungan. Lebih lanjut, kajian ekologi politik juga akan menelusuri penyebab degradasi lingkungan dengan mempertimbangkan skala yang lebih luas, seperti peran negara dan pasar global (bukan sekedar melihhat dari aktor setempat yang terkait bencana).
Berkaitan dengan kerentanan dan ancaman resiko bencana akibat perubahan iklim, tiap-tiap masyarakat dalam suatu sistem sosial tertentu memiliki ciri (pencegahan, kesiapapsiagaan dan respons) yang berbeda dalam menanggapi bencana. Selain itu, kelompok masyarakat tertentu juga memiliki kerentanan dan daya pemulihan yang berbeda pula satu sama lain. Sehingga, faktor-faktor diluar alamiah pun tidak dapat dihindarkan dalam mengkaji suatu bencana. Perbedaan atau ketimpangan kondisi tersebut dapat ditentukan oleh beberapa perbedaan dalam kelompok sosial tertentu, seperti kelas, gender, etnis, atau juga kondisi disabilitas. Belum lagi, hal tersebut lebih luas juga dipengaruhi oleh kekuatan global yang ada, misalnya pola penyebaran informasi, akses terhadap pasar dunia, tekanan ekonomi global, perang, urbanisasi dan pertumbuhan penduduk.
Dengan begitu dapat kita lihat bahwa kajian kebencanaan sangat erat sekali dengan isu-isu politis dari aktor-aktor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga, fenomena alam (perubahan iklim) menjadi isu-isu penting dalam kajian ekologi politik sebagaimana alam bukan hanya dimaknai secara fisik tapi juga dikonstruksi secara sosial. Pada tataran yang lebih jauh, hadirnya perubahan iklim sebagai wacana global akhirnya memaksa berbagai pihak untuk melakukan mitigasi perubahan iklim tersebut. Kemudian hal itu diharapkan memunculkan kemampuan adaptasi dan ketahanan manusia, akan tetapi disisi lain hal tersebut juga dilihat sebagai peluang ekonomi para kapitalis dalam mengkomodifikasi produknya. Hal-hal semacam itu yang seharusnya diimbangi dengan kemampuan kebijakan nasional dan negosiasi internasional, khususnya dalam mengendalikan pasar.
PEMBAHASANPERUBAHAN IKLIM (Anthony Giddens)Sebagaimana yang diungkapkan oleh Giddens tentang juggernaut modernitas yang mana kapitalisme dan industrialisme menjadi mesin yang terus berjalan dan menggilas apa saja yang ada didepannya. Hal tersebut menisyaratkan terjadinya mengeksploitasi SDA dengan skala besar demi kepentingan ekonomi produksi. Hal itu menurutnya berkonsekuensi negatif terhadap kehidupan manusia. Akhirnya degradasi lingkungan pun terjadi dan perubahan iklim pun tidak dapat dihindarkan. Untuk menghadapi permasalahan perubahan iklim, Giddens mengusulkan suatu kerangka kerja politik. Ia beranggapan bahwa masyarakat masih belum begitu sadar dan kurang kuatir terhadap resiko di masa depan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat masih meraba-raba resiko bencana yang belum pasti dan abstrak. Oleh karena itu, masyarakat harus dimotivasi untuk dapat terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam mitigasi perubahan iklim. Motivasi positif tersebut dilakukan dengan cara mengubah gaya hidup yang lebih ramah terhadap lingkungan, kegiatan ekonomi karbon rendah dan diikuti dengan keamanan energi yang lebih tinggi.
Giddens dalam bukunya The Politics of Climate Change, hadirnya ilmu pengetahuan yang diiringi dengan tindakan yang tidak etis terhadap sumberdaya alam menimbulkan problema tersendiri yang tidak langsung dirasakan efeknya. Konsekuensi negatif tersebut berupa ancaman yang tidak nyata dan tidak segera terjadi (immediate). Ancaman tersebut diperburuk pula dengan adanya sistem nilai pasar sebagai acuannya. Oleh karena itu, upaya dalam mereduksi ancaman perubahan iklim dapat dilakukan dengan upaya politis melalui wacana dan mobilisasi global dalam skala multinasional agar nantinya proses-proses pembangunan juga sejalan atau konsisten dengan harapan-harapan yang ada. Untuk mensdtabilkan keadaan ini, Giddens juga mengusulkan dibentuknya suatu lembaga baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengatur dan mengarahkan kondisi dunia. Dengan demikian, dampak perubahan iklim dapat diminimalisir.
MODERNISASI EKOLOGI VS IDEOLOGI HIJAU (James Connely and Graham Smith)
Dalam buku Politic and Environmemtal James Connely dan Graham Smith banyak menyinggung mengenai pembangunan berkelanjutan, dimana dalam pembangunan berkelanjutan tersebut aspek utama yang dibahas adalah mengenai permasalahan ekonomi dan lingkungan, dimana kedua aspek tersebut saling mempengaruhi. Di era modern saat ini pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terus berkembang pesat, maka dari itu muncullah gagasan modernisasi ekologi, dimana pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan bukanlah dua hal yang saling meniadakan (mutually exclusive). Dalam modernisasi ekologi, pembangunan ekonomi tetap bisa berjalan dengan efisien dan juga kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat dicegah atau dihindari.Namun hal ini mendapat penolakan dari kalangan hijau, bagi kalangan hijau pembangunan berkelanjutan tidak akan bisa dicapai tanpa perubahan fundamental pada ekonomi, politik, struktur dan tatanan kehidupan sosialnya. Karena pada realitasnya, pembangunan berkelanjutan yang nampak pada saat ini adalah sebuah pembangunan yang hanya mengedepankan aspek ekonominya saja, pembangunan yang hanya memenuhi kebutuhan pada masa kini saja, tanpa mempertimbangkan bagaimana nasib generasi mendatang.
Inti cita-cita dan tema dalam pembangunan berkelanjutan:
1. Integrasi ekonomi - lingkungan: Keputusan ekonomi harus memperhatikan konsekuensi lingkungan mereka.
2. Kewajiban antar generasi: Saat ini putusan dan praktik untuk mempertimbangkan efek dari mereka pada masa depan generasi .
3. Keadilan sosial: Semua orang memiliki hak yang sama untuk suatu lingkungan di mana mereka dapat berkembang .
4. Perlindungan environmental: Konservasi sumber daya dan perlindungan manusia dunia .
5. kualitas dari kehidupan: Pengertian yang lebih luas dari kesejahteraan manusia di luar sempit didefinisikan kesejahteraan ekonomi .
6. Partisipasi: Lembaga menjadi menstrukturkan kembali untuk mengijinkam semua suara untuk didengar dalam pengambilan keputusan. ( diadaptasi dari Jacobs, 1995a,p. 1471 ) `
Konsep pembangunan berkelanjutan adalah mendasar, karena mewujudkan berbagai cita-cita dan realisasi prinsip-prinsip yang diperlukan untuk sebuah masa depan hijau. Ide pembangunan berkelanjutan akan menjalankan tema yang mengaitkan bagian dan bab dari buku.Terdapat 3 instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk merespon masalah lingkungan yang timbul, yaitu:
Kebijakan atur-kendali yang diterapkan melalui penetapan peraturan perundangan yang bersifat wajib ditaati oleh masyarakat.
Penerapan instrumen ekonomi sebagai insentif untuk menjalankan pengelolaan lingkungan hidup.
Pendekatan sukarela (atur diri sendiri) yang bertujuan untuk merubah sikap dan nilai.
Gagasan modernisasi ekologi sendiri muncul di kalangan pengusaha dan pemerintah, dimana mereka memandang pada modernisasi ekologi inilah yang merupakan titik masu diintegrasikannya pertimbangan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan sosial, ekonomi dan politik. Integrasi ini berlangsung dalam konteks green capitalist framework, dan seluruh pihak baik pemerintah, pengusaha dan LSM dilibatkan dalam proses penerapan kebijakan.
Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan kaum hijau radikal (green radical), ia menolak modernisasi ekologi sebagai solusi atas pembangunan berkelanjutan, karena bagi kaum hijau radikal pembangunan berkelanjutan tidak bisa dicapai tanpa adanya perubahan yang fundamental pada struktur, institusi, tatanan nilai dan praktek dalam kehidupan kehari-hari.
Menurut James Connely dan Graham Smith solusi atas permasalahan pembangunan berkelanjutan tersebut adalah Demokratisasi Ekologi, demokratisasi yang dimaksudkan disini adalah demokratisasi atas institusi ekonomi, sosial dan politik di semua level yang ada pada saat ini. Dengan demokrasisasi tersebut dapat tercipta sebuah kebijakan pembangunan yang berkeadilan. KEADILAN EKOLOGI (Nicholas Low dan Brendan Gleeson)
Paradigma tentang ekologi politik yang telah dibahas oleh tokoh sebelumnya telah mengantarkan kita untuk mempelajari pula mengenai keadilan ekologi yang dipaparkan oleh Nicholas Low dan Brendan Gleeson. Dalam inti dari pembahasan ini kita dapat mempelajari mengenai pentingnya keadilan ekologi dalam ekologi politik. Keadilan ekologi merupakan suatu bentuk dari pendistribusian kekuasaan terhadap lingkungan dengan membaginya pada seluruh makhluk yang berada diplanet ini (Low and Gleeson, 2002). Menyadari bahwa hidup didalam lingkungan tidak hanya terdapat manusia yang sebagai makhluk hidup saja, namun juga terdapat benda lain baik biotik maupun abiotik yang memerlukan keberlangsungan hidup dalam lingkungan ini. Dengan demikian, manusia yang merasa dirinya sebagai makhluk yang paling sempurna dan berakal lebih dominan untuk menguasai lingkungan tanpa memperhatikan keberlangsungan hidup makhluk lainnya. Hal ini merupakan suatu fenomena yang dapat merugikan berbagai pihak jika manusia tidak disadarkan dengan keadilan ekologi yang sejatinya membahas pula mengenai etika atau moral terhadap lingkungan. Lingkungan dalam perspektif ini perlu diperdalam lagi pengertiannya sehingga kita bisa sadar bahwa diperlukannya etika yang kita terapkan pada non dunia manusia.
Relasi yang kuat antara keadilan, masyarakat dan alam merupakan suatu bentuk nyata bahwa didalam lingkungan ini memerlukan suatu keadilan sehingga tidak ada dominasi yang dapat menjatuhkan lainnya. Sebagaimana isu-isu yang berkembang saat ini mengenai perubahan iklim, bencana lingkungan dan sebagainya merupakan hal yang sejatinya dapat diminimalisir jika para aktornya sadar akan keadilan ekologi. Keadilan ekologi tidak hanya sekedar wacana yang dapat mengantisipasi isu-isu demikian, namun keadilan ekologi ini memerlukan suatu tindakan nyata yang dapat diwujudkan oleh para aktor. Konsep keadilan ekologi yang menekan pentingnya moral atau etika terhadap lingkungan ini dapat mewujudkan pula pada pembangunan berkelanjutan yang telah digagas pada awal tahun 1980. Dari perwujudan keadilan ekologi ini akan mengantarkan para aktor untuk sadar dan turut serta menjaga lingkungannya sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.
Realita yang berkembang selama ini, manusia memiliki kekuatan yang paling besar dalam mengelola lingkungan yang ditempati oleh berbagai makhluk. Dengan adanya kekuatan tersebut manusia dapat menggunakan lingkungan menjadi ladang penghidupannya hingga dapat merusak lingkungan. Hal ini tidak dapat dielak lagi dengan adanya berbagai kasus seperti pembalakan hutan yang menyebabkan deforestasi hingga degredasi lahan, yang hanya dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi keuntungan tertentu. Krisis ekologi global yang dialami oleh manusia seperti ini secara mendasar bersumber pada fundamental-filosofis dalam pemahaman cara manusia mengenai dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Manusia keliru memandang alam, dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta seluruhnya ( Keraf, 2002). Sehubungan dengan itu maka lingkungan sering dijadikan korban, karena rusaknya etika dan mungkin kurangnya pengetahuan dari orang-orang tersebut. Rusaknya etika dalam sistem dunia menghambat dialektika keadilan lingkungan untuk memperluas diri dan merangkul lingkungan serta makhluk non-manusia (Low and Gleeson, 2009). Tawaran menggunakan konsep keadilan ekologi merupakan jawaban yang tepat sehingga manusia dapat merubah pandangannya mengenai kekuasaannya terhadap lingkungan. Keadilan ekologi yang di paparkan oleh Nicholas Low dan Gleeson merupakan suatu cara yang bertujuan untuk menyelamatkan lingkungan dan menyadarkan pada manusia mengenai etika atau moral mereka yang selama ini banyak merugikan berbagai pihak. Penggunaan konsep keadilan ekologi ini dapat dimulai dengan adanya kesadaran manusia untuk menjaga lingkungan beserta makhluk didalamnya hingga melanjutkannya dengan konsep pembangunan keberlanjutan.
ILMU PENGETAHUAN DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN (Ann Campbell keller)
Jika kita berbica tentang lingkungan, maka tidak akan lepas hubungannya dengan politik lingkungan. Dalam pembahasan lingkungan dan kaitannya dengan ilmu pengetahuan, ada aktor yang tidak nampak secara jelas memainkan politiknya dengan menggunakan isu lingkungan, aktor ini adalah ilmuwan. Dengan mengacu pada dasar yang mengatakan bahwa ilmu pengeahuan adalah hal yang penting dan dipercaya oleh masyarakat, maka niscaya seorang ilmuwan menjadi aktor yang mendapat legitimasi dari masyarakat. Ilmuwan dianggap sebagai orang yang mempunyai kefakihan khusus terhadap suatu bidang. Sebelum jauh membahas tentang permainan politik oleh aktor para ilmuwan, akan lebih baik jika kita bahas dahulu tentang dua pandangan mengenai permasalahan ini, yaitu pandangan rasionalis dan pandangan positivis. Pandangan rasionalis memandang bahwa ilmu pengetahuan sangat diperlukan dalam ranah kebijakan. Dalam pandangan rasionalis ini, ilmu pengetahuan dipandang dapat menyumbangkan analisanya mengenai kondisi-kondisi sosial dan lingkungan saat ini dan dimasa depan, juga dapat memberikan cara-cara untuk mencapai tujuan. Sedangkan pandangan positivis, berangggapan bahwa keterlibatan ilmu pengetahuan dalam ranah pembuatan kebijakan hanyalah sebagai mekanisme yang ditujukan untuk kepentingan politik. Nah, dalam ruang inilah kita akan mengupas lebih dalam bagaimana permainan politik aktor dengan dilatarbelakangi oleh ilmu pengetahuan.
Dalam permaslahan lingkungan, berikut korelasinya dengan pembuatan kebijakan mengenai lingkungan, nampaknya masyarakat kita menganut pandangan rasionalis yang menjunjung ilmu pengetahuan sebagai sumber pemecahan masalah, termasuk didalamnya permasalahan kebijakan lingkungan. Para ilmuwan mendapat legitimasi yang sangat kuat dari masyarakat untuk memecahkan permasalahan atau isu lingkungan. Para ilmuwan yang fakih dalam bidang lingkungan berlomba mengembangkan penelitian dan berusaha membuat temuan baru tentang alam dan lingkungan. Temuan yang dihasilkan merupakan klaim, jika disebut dalam buku karya Ann Campbell Keller, temuan seorang ilmuwan disebut juga dengan narasi ilmuwan. Narasi ilmuwan yang didalamnya terdapat narasi pengetahuan adalah suatau hal yang diakini benar oleh masyarakat luas dan dianggap sebagai isu lingkungan yang nyata adanya. Sauatu klaim ilmuwan kadang terima begitu saja oleh pembuat kebijakan tanpa memberikan pengujian. Klaim atau temuan yangtelah ada ini selanjutnya akan diproses secara institusional lalu dituangkan dalam kebijakan. Kemudian dalam proses pembuatan kebijakan ini dibuat sebuat sebuat program mitigasi lingkungan. Pertanyaannya adalah, apakah klaim yang diberikan para ilmuwan itu benar obyektif? Karena dalam proses penyataanya, narasi atau klaim tersebut menjadi sebuah media dimana seorang ilmuwan berusaha menyatakan pandangannya sebagai realita, atau dalam kata lain, klaim yang berupa naratif manjadi argumentatif. Seorang ilmuwan mem-publish klaimnya tersebut dengan berusaha membuat masyarakat percaya dan menganggapnya sebagai realita dan kebenaran.
Dari pemaparan diatas, dapat didefinisikan bahwa ilmu pengetahuan sendiri memiliki posisi otoritas dalam pembuatan kebijakan. Dan yang paling penting adalah aktornya yaitu ilmuwan yang juga mendapat posisi yang strategis untuk dipercaya sebagai sumber dan dasar dibuatnya kebijakan mengenai lingkungan. Jika kita amati secra jeli, para ilmuwan telah memainkan politik kepentingannya dengan mendefinisikan dirinya sebagai solusi permasalahan lingkungan dengan klaim-klaim dan temuannya. Mari kita meruntutkan permasalahan ini dengan kasus yang terjadi.
Peristiwa alam hujan asam tentu sudah tidak asing ditelinga kita. Hujan asam pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris Jhon Evelyn yang kemudian ia menulis dalam bukunya pada tahun 1961, dan kemudian ia mem-publish tulisannya tentang hujan asam dan kerugian yang terjadi akibatnya. Lalu dengan berkembangnya penelitian tentang hujan asam, banyak ilmuwan yang membentuk perkumpulan khusus untuk meneliti tentang hujan asam. Sampai pada akhirnya pemerintah USA pertamakali melakukan aksinya dengan membentuk kongres yang membahas tentang hujan asam dan dampak kesehatan pada manusia. Dalam kongres tersebut dilibatkan banyak ilmuwan untuk meneliti dan menangani gejala alam hujan asam. Karena dirasa penelitian ini penting, maka masyarakat pun mencurahkan dana untuk penelitian ini. hal yang hampir sama juga terjadi di Swedia oleh Svente Oden. Ia melakukan penelitian tentang hujan asam, ia menggambarkan tentang limnology, atmospheric chemistry, dan penelitian agrikultur untuk menjelaskan pemahaman tentang penyebab dan efek dari hujan asam. Setelahnya, ia mempublish hasil penelitiannya di Swedish newspaper Dagens Nyheter dan Swedens Ecology Committee Bulletin. Lalu dari kedua publikasi Oden, pemerintah Swedia merespon dan membuat sebuah studi kasus yang dituangkan dalam United Nations Conference on the Human Environment. Penelitian tentang hujan asam nampaknya semakin berkembang dan banyak yang menaruh minat padanya, ilmuwan di Amerika Utara juga melakukan penelitiannya tentang efek dari peleburan logam pada lingkungan.
Dari contoh kasus ini jelas terlihat bahwa para ilmuwan dengan narasi pengetahuannya sedang melakukan politik kepentingannya terhadap lingkungan. Dapat juga terlihat bahwasanya pengetahuan dapat menentukan kebijakan yang dibentuk oleh suatu Negara dan masyarakat. Pada kasus hujan asam, para ilmuwan dibanyak daerah saling berlomba-lomba untuk mengambangkan penelitiannya, mereka bersama-sama menunjukkan pada masyarakat tentang penemuannya tentang gejala yang terjadi pada lingkungan. Dengan legitimasinya, pemerintah merespon dan memperhatikan hasil penelitian-penelitianpara ilmuwan tersebut untuk dijadikan kebijakan formal.POLITICS OF NATURE (Bruno Latour) Isu-isu mengenai politik alam telah hadir di Negara maju dan juga Negara berkembang. Ketika menyebutkan politik, kita seringkali mendefinisikan bahwa politik berkaitan dengan konflik, perebutan kekuasaan, ketidaksetaraan dan distribusi sumberdaya serta kekayaan, dan lain-lain. Namun dalam pembahasan kali ini yang dimaksud dengan politik tidak seperti definisi diatas melainkan politik yang berhubungan dengan alam. Dalam membahas politik alam, Bruno Latour menerbitkan buku politics of nature. Latour mengatakan bahwa orang-orang modern tidak siap dalam menangani krisis ekologi dan dia menginginkan seseorang turun ke bumi yang artinya seseorang harus segera menangani krisis ekologi. Ekologi politik sendiri masih baru dan belum mulai eksis karena masyarakat lebih mengandalkan konsep-konsep lama mengenai alam.
Dalam jurnalnya yang berjudul politics of nature : east and west perspective Latour berbicara mengenai iklim. Iklmi sangat penting untuk diperhatikan karena sangat berpengaruh pada kehidupan. Misalnya dari bidang pertanian, seperti cuaca, curah hujan, dll butuh dipertimbangkan. Perubahan iklim juga berpengaruh pada perubahan musim hujan, polusi, tanah dan lainnnya. Perubahan iklim yang buruk menyebabkan bumi bermasalah. Dalam melindungi alam atau melindungi ciptaan kita seringkali mengedepankan rasa malas, bosan dan santai. Latour menginginkan kita membuang sifat-sifat tersebut karena kita hidup dibumi dan bumi membutuhkan kita. Dalam masalah yang berhubungan dengan alam, manusia seringkali tidak memiliki sikap yang greget untuk mengatasinya. Kita seringkali merasa terancam dengan masalah-masalah ekologi namun orang ekologis atau orang yang peduli dengan ekologi jumlahnya selalu minoritas. Meskipun ini era modernisasi, namun orang-orang modern ternyata tidak siap menghadapi masalah ekologi. Mereka bingung dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan alam karena kurangnya pengetahuan mengenai politik alam itu sendiri.
CONTOH KASUS:
Contoh kongkrit dari politik lingkungan yang ada pada saat ini adalah Protokol Kyoto, Protokol kyoto merupakan sebuah instrumen hukum yang dirancang untuk mengimplementasikan konvensi perubahan iklim yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi GRK agar tidak menganggu sistem iklim bumi.
Protokol kyoto ditandatangani pada tanggal 11 desember 1997, protokol tersebut secara efektif akan berlaku 90 hari setelah diratifikasi oleh setidaknya 55 pihak konvensi, termasuk negara-negara maju dengan total emisi karbon dioksida paling sedikit 55% dari total emisi tahun 1990 dari kelompok negara-negara industri tersebut.
Protokol Kyoto dan secara teknis dapat berpartisipasi melalui salah satu dari tiga mekanisme kyoto, yaitu:
mekanisme pembangunan bersih (CDM), negara yang memiliki komitmen atas pembatasan emisi di bawah perjanjian Protokol Kyoto untuk melaksanakan targetnya yaitu pengurangan emisi di negara berkembang.
joint implementation (JI), negara penghasil emisi mendapatkan proyek penurunan emisi bukan di negara berkembang tetapi di sesame negara penyumbang emisi terbesar.
Emission trading (ET), perdagangan karbon dengan cap and trade system dimana negara yang telah dibatasi emisinya diperbolehkan memperdagangkan karbon dengan satuan Assigned Amount Units (AAUs)
Protokol yang merupakan dasar bagi negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca gabungan mereka paling sedikit 5% dari tingkat emisi tahun 1990 menjelang periode 2008-2012. Protokol kyoto disusun untuk mengatur target kuantitatif penurunan emisi dan target waktu penurunan emisi bagi negara maju (Murdiyarso, 2003).
Protokol tersebut dibuat agar negara-negara maju penyumbang emisi gas terbanyak dapat berperan aktif dan usaha konservasi lingkungan.
Terdapat 2 kategori perjanjian pada Protokol Kyoto, yaitu:
Annex: negara maju penghasil emisi terbanyak
Non- Annex: negara yang menandatangani perjanjian tetapi tidak memiliki kewajiban menurunkan emisi, golongan Non-Annex kebanyakan berasal dari negara berkembang yang masih memiliki hutan.ANALISA:
Adanya Protokol Kyoto merupakan salah satu bukti adanya politisasi yang di latarbelakangi oleh faktor lingkungan. Protokol Kyoto sendiri ditanda tangani oleh setidaknya 50 negara yang ada didalamnya, perjanjian ini dilatar belakangi oleh munculnya kesadaran atas keadaan alam yang semakin memprihatinkan akibat mesin-mesin produksi skala besar yang terus mengeluarkan gas emisi yang akan berdampak buruk bagi bumi. Jika tidak cepat ditangani maka asap-asap yang terus mengepul dari cerobong-cerobong raksasa tersebut akan semakin membahayakan karena dapat merusak lapisan ozon dan juga sangat membayakan bagi kehidupan manusia karena udaranya sudah tercemar.
Maka dari itu dibuatlah sebuah perjanjian diantara negara-negara, baik negara maju penyumbang karbon dioksida maupun negara berkembang yang notabanenya masih memiliki hutan yang luas sebagai filter karbon dioksida tersebut dan juga sebagai paru-paru dunia.
Dalam perjanjian tersebut terdapat 2 kategori, yaitu: negara annex, negara yang menyumbang gas emisi terbanyak dan non-annex, negara yang memiliki kewajiban untuk menurunkan gas emisi. Negara non-annex akan dibiaya untuk melakukan konservasi hutan dan usaha-usaha lainnya yang bisa menurunkan atau menyerap gas emisi yang dihasilkan negara annex.
SUMBER:http://digilib.uin-suka.ac.id/9404/1/BAB%20I.%20V.pdfhttp://www.atmajaya.ac.id/web/KontenFakultas.aspx?gid=riset-publikasi-fakultas&ou=fiabikom&cid=MARTABAT-PEJABAT-PUBLIKhttp://www.digilib-ampl.net/detail/detail.php?row=0&tp=artikel&ktg=climate&kd_link=&kode=2509Giddens, Anthony (2009) The Politics of Climate Change. Cambridge: Polity (publisher)
Murdiyarso, Daniel. 2003. Protocol Kyoto : Implikasinya Bagi Negara Berkembang. Jakarta : Kompas Media NusantaraJames Connely, Graham Smith. 2001. Politic and The Environment From Theory To Practice. Canada: Taylor & Francis e-Library
Soeryo Adiwibowo. Bedah buku: Politics and the Environment: From Theory to Practice. http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/5933.pdf. Diakses pada 21 februari 2015Bruno Latour, Politics of Nature : East and West Perspective, ParisKeraf, Sony. 2010. Etika Lingkungan Hidup. Kompas
Low, Nichole and Gleeson Brendan. 2002. Justice, Society and Nature An Exploration of Political Ecology. Routledge : London and New York
Low,Nichole and Gleeson Brendan.2009. Politik Hijau. Nusa Media : Bandung