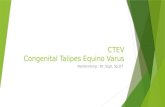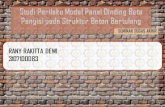Laporan Kasus Ctev Rany
-
Upload
rany-ramadhani-kusuma-sejati -
Category
Documents
-
view
932 -
download
184
Transcript of Laporan Kasus Ctev Rany

BAB I
PENDAHULUAN
I. IDENTITAS
a. IdentitasPasien
Nama : An. Ilham
Umur : 16 Bulan
Jeniskelamin : Laki-laki
Agama : Islam
BB masuk : 10 Kg
Alamat : Panambangan
b. Identitas Orang Tua
a. Ayah
Nama : Tn. Wawan
Umur : 30 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang
b. Ibu
Nama : Ny. Icih
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
1

II. ANAMNESIS (ALLOANAMNESIS)
A. Keluhan Utama
Kaki sebelah kanan pengkor
B. Riwayat Penyakit Sekarang
Pada tanggal 12 Februari 2014 penderita dibawa orang tuanya ke poli
orthopedic RS. W dengan keluhan kaki sebelah kanan pengkor. Orang tua
Os mengaku hal ini sudah dialami Os semenjak lahir. Ibu os menceritakan
bahwa bengkok hanya di bagian tungkai bawah. Os saat ini sudah bisa
berjalan.
C. Riwayat Penyakit Keluarga
Dikeluarga tidak ada yang memiliki riwayat penyakit yang sama dengan
yang dialami Os .
D. Riwayat Trauma
OS tidak memiliki riwayat trauma sebelumnya.
E. Riwayat Kehamilan
Kehamilan selama 9 bulan, selama OS dalam kandungan ,ibu OS rajin
memeriksakan kandungannya ke bidan setiap bulan, ibu OS tidak terdapat
riwayat merokok atau mengkonsumsi alkohol. Riwayat penyakit ibu saat
hamil tidak ada, kelainan selama kehamilan tidak ada. Ibu Os mengaku
tidak pernah terjatuh ataupun mengalami benturan di daerah perut selama
masa kehamilan.
2

F. Riwayat Persalinan
Cara lahir : Melalui per vaginal / lahir spontan
Ditolong oleh : Bidan
BB/PB lahir : 3,2 Kg / 50 cm
Pasien anak ke 1 dari 0 saudara
G. Riwayat Imunisasi
Jenis Imunisasi Ke Usia Keterangan
BCG 1 0 bulan Sudah
Hepatitis B 1
2
3
0 bulan
1 bulan
6 bulan
Sudah
Sudah
sudah
DPT 1
2
3
2 bulan
3 bulan
4 bulan
Sudah
Sudah
Sudah
Polio 1
2
3
0 bulan
2 bulan
3 bulan
Sudah
Sudah
Sudah
Campak 1 9 bulan Sudah
H. Riwayat Makanan
0 – 5 Bulan : ASI
5 – 7 Bulan : ASI + Bubur susu
6 – 9 bulan : ASI + Bubur susu
9 – 12 bulan : ASI + Bubur saring
12 bulan – sekarang : Susu formula + Menu keluarga
3

I. Tumbuh Kembang Anak
a. Lahir : Menangis
b. 0 - 3 Bulan : Belajar mengangkat kepala
c. 3 - 6 Bulan : Berusaha meraih benda-benda
d. 6 - 9 Bulan : Tengkurap dan berbalik sendiri
e. 9 - 12 Bulan : Belajar berdiri
f. 12 – Sekarang : Berjalan tanpa dituntun
Kesan : perkembangan baik
III. PEMERIKSAAN FISIK
A. KeadaanUmum
Tampak sakit sedang
B. Kesadaran
Compos mentis
C. Tanda-tanda Vital
Frekuensi nadi : 120 x/menit
Frekuensi napas : 28 x/menit
Suhu : 36,8 °C
D. Status Gizi
BB : 10 Kg
PB : cm
Kesan :Gizi Cukup
4

E. Status Generalisata
a. Kepala
Bentuk : Mesochepalica
Ukuran : Normochepalica
Rambut : Hitam, tidak mudah di cabut
Mata : Pupil bulat isokor, Konjungtiva anemis -/- , Sclera
ikterik -/-
Telinga :Bentuk normal
Hidung : Bentuk normal, Pernapasan cuping hidung (-), Sekret
(-)
Mulut : Bibir kering (-), Sianosis (-)
Tenggorokan: Faring hiperemis (-)
Leher : Pembesaran KGB (-), Peningkatan JVP (-)
b. Thorax
Paru
Inspeksi : Bentuk dan gerak simetris, jejas (-), pernapasan
tertinggal (-), retraksi sprasternal (-), retraksi intracostal
(-), retraksi subcostal (-).
Palpasi : Vocal fremitus sulit dinilai
Perkusi : Sonor
Auskultasi :Suara napas Bronkial, ronki basah kasar diseluruh
lapang paru, wheezing (+) kanan dan kiri.
5

Jantung
Inspeksi : Ictus cordis tidak terlihat
Palpasi : Ictus cordis tidak teraba
Perkusi : Batas jantung pada sternal kanan ICS 2 (katup aorta),
sternal kiri ICS 2 (katup pulmonal), sternal kiri ICS 3-4
(katup trikuspid), sternal kiri mid klavikula ICS 5
(katup mitral)
Auskultasi : Bunyi jantung I II murni regular, Gallops (-), Murmur
(-)
c. Abdomen
Inspeksi : Cembung, Simetris
Auskultasi : Bising Usus (+) normal
Palpasi : Soepel, Defans muscular (-), Turgor kembali cepat,
Hepar dan lien tidak teraba
Perkusi : Timpani seluruh lapang, , asites (-)
d. Genitalia
Dalam batas normal
F. Status Lokalis (Eksremitas Bawah)
Kanan
Look : Tampak deformitas equinus (+), varus (+), warna sama dengan kulit
sekitar, luka (-), oedem (-), shortening (+), angulasi medial (+)
Feel : Nyeri tekan (-), suhu sama dengan suhu tubuh, krepitasi (-),
sensibilitas (-), pulsasi dorsalis pedis (+), crt < 2 dtk
6

Move : Gerakan aktif
Kiri
Look : Tampak deformitas equinus (-), varus (-), warna sama dengan kulit
sekitar, luka (-), oedem (-),shortening (-),angulasi medial (-)
Feel : Nyeri tekan (-), suhu sama dengan suhu tubuh, krepitasi (-),
sensibilitas (-), pulsasi dorsalis pedis (+), crt < 2 dtk
Move : Gerakan aktif
Pemeriksaan Eksremitas
Motorik Superior Inferior
Gerak +/+ +/+
Kekuatan 5/5 5/5
Sensibilitas +/+ +/+
Reflek Patologis -/- -/-
Edema -/- -/-
7

G. FOTO KLINIS
H. FOTO RONTGEN
8

I. USULAN PEMERIKSAAN
Laboratorium darah lengkap (Hb, leukosit, LED, trombosit, glukosa
sewaktu, ureum, kreatinin)
Foto thorax
Foto tarsal AP - Lateral
J. DIAGNOSIS KERJA
Congenital Talipes Equinovarus (CTEV)
9

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. LATAR BELAKANG
Bayi yang lahir dengan keadaan sehat serta memiliki anggota tubuh yang
lengkap dan sempurna merupakan harapan dari seorang Ibu dan seluruh keluarga.
Namun terkadang pada beberapa keadaan tertentu didapati bayi yang lahir kurang
sempurna karena mengalami kelainan bentuk anggota tubuh. Salah satu kelainan
adalah kelainan bawaan pada kaki yang sering dijumpai pada bayi yaitu kaki bengkok
atau CTEV(Congenital Talipes Equino Varus). CTEV adalah salah satu anomali
ortopedik kongenital yang sudah lama dideskripsikan oleh Hippocrates pada tahun
400 SM (Miedzybrodzka,2002).
CTEV atau biasa disebut Clubfoot merupakan istilah umum untuk
menggambarkan deformitas umum dimana kaki berubah/bengkok dari keadaan atau
posisi normal. Beberapa dari deformitas kaki termasuk deformitas ankle disebut
dengan talipes yang berasal dari kata talus (yang artinya ankle) dan pes (yang berarti
kaki). Deformitas kaki dan ankle dipilah tergantung dari posisi kelainan ankle dan
kaki. Deformitas talipes diantaranya :
Talipes Varus : inversi atau membengkok ke dalam.
Talipes Valgus : eversi atau membengkok ke luar.
Talipes Equinus : plantar fleksi dimana jari-jari lebih rendah daripada tumit.
Talipes Calcaneus : dorsofleksi dimana jari-jari lebih tinggi daripada tumit.
Clubfoot yang terbanyak merupakan kombinasi dari beberapa posisi dan
angka kejadian yang paling tinggi adalah tipe Talipes Equino Varus (TEV) dimana
kaki posisinya melengkung ke bawah dan ke dalam dengan berbagai tingkat
10

keparahan. Unilateral clubfoot lebih umum terjadi dibandingkan tipe bilateral dan
dapat terjadi sebagai kelainan yang berhubungan dengan sindroma lain seperti aberasi
kromosomal, artrogriposis (imobilitas umum dari persendian), cerebral palsy atau
spina bifida.
Frekuensi clubfoot dari populasi umum adalah 1:700 sampai 1:1000 kelahiran
hidup dimana anak laki-laki dua kali lebih sering daripada perempuan. Berdasarkan
data, 35% terjadi pada kembar monozigot dan hanya 3% pada kembar dizigot. Ini
menunjukkan adanya peranan faktor genetika. Insidensi pada laki-laki 65% kasus,
sedangkan pada perempuan 30-40% kasus. Pada pasien pengambilan cairan amnion,
deformitas ekstrimitas bawah kira-kira mencapai 1-1,4% kasus. Sedangkan pada ibu
yang mengalami pecah ketuban kira-kira terdapat 15% kasus. Epidemiologi CTEV
terbanyak pada kasus-kasus amniotik.
11

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. DEFINISI
Congenital Talipes Equino Varus (CTEV) adalah deformitas yang meliputi
fleksi dari pergelangan kaki, inversi dari tungkai, adduksi dari kaki depan, dan rotasi
media dari tibia.1 Congenital Talipes Equino Varus adalah fiksasi dari kaki pada posisi
adduksi, supinasi dan varus. Tulang calcaneus, navicular dan cuboid terrotasi ke arah
medial terhadap talus, dan tertahan dalam posisi adduksi serta inversi oleh ligamen
dan tendon. Sebagai tambahan, tulang metatarsal pertama lebih fleksi terhadap daerah
plantar.2
B. ETIOLOGI
Sampai sekarang, penyebab dari deformitas ini masih belum dapat dipastikan,
meskipun demikian dikemukakan berbagai macam teori tentang hal itu. Antara lain:1,3,5
1. Mekanik
12

Teori ini merupakan teori tertua yang dikemukakan oleh Hippocrates yang
menyatakan bahwa posisi equinovarus kaki fetus disebabkan oleh tekanan mekanik
eksternal. Teori ini diperkuat oleh observasi bahwa insiden CTEV tidak meningkat pada
kondisi lingkungan prenatal yang cenderung membuat uterus terlalu penuh, seperti
kembar, janin besar, primipara, hydramnion dan oligohidramnion. Teori ini
bertentangan dengan teori kedua tentang faktor lingkungan intrauterin berikut ini.
2. Environmental
Browne (1936) menyatakan teori peningkatan tekanan intrauterin yang
menyebabkan imobilisasi ekstremitas sehingga menyebabkan deformitas. Teori lain
adalah perubahan ukuran uterus atau karena bentuk, seperti misalnya terdapat
lekukan pada konveksitas uterus dan oligohydramnion.
Karena obat-obatan, seperti yang sering ditemukan pada ‘thalidomide baby’
3. Herediter
Wynne-Davies (1964) meneliti lebih dari 100 penderita dan generasi pertamanya.
Didapatkan hasil bahwa deformitas tersebut terjadi pada 2,9% saudara kandung.
Sedangkan pada populasi umum terdapat 1 : 1000 kelahiran.
Idelberger meneliti pada anak kembar dan mendapatkan angka 32,5% penderita
CTEV pada kembar monozygotik dan 2,9% pada dizygotik. Angka terakhir sama
seperti insiden pada saudara kandung bukan kembar.
4. Idiopatik
Böhm menyatakan teori terhambatnya perkembangan embrio. Kaki embrio normal
saat usia 5 minggu kehamilan dalam posisi equinovarus, jika terjadi terhambatnya
perkembangan kaki pada salah satu fase fisiologis dalam kehidupan embrio, maka
deformitas ini akan persisten hingga kelahiran.
Terdapat 4 fase dalam evolusi kaki manusia saat pertengahan kehidupan prenatal, yaitu:
13

Fase I (Bulan ke-2): bentuk kaki dalam posisi equinus berat (plantarfleksi ± 90º). Dan
adduksi hind dan forefoot yang berat.
Fase II (Awal bulan ke-3): kaki berotasi ke posisi supinasi, tetapi tetap
plantarfleksi 90º, adduksi metatarsal.
Fase III (Pertengahan bulan ke-3): Inklinasi equinus berkurang menjadi derajat
ringan, posisi supinasi dan varus metatarsal tetap.
Fase IV (Awal bulan ke-4): Kaki dalam posisi midsupinasi dan varus metatarsal
yang ringan. Pada fase ini, secara bertahap, bidang kaki dan tungkai bawah mulai
tampak dalam posisi seperti kaki dewasa.
5. Defek neuromuskular dan tulang prenatal
Gangguan anatomik intrisik pada sendi talocalcaneus dan pada inervasi m. peroneus
karena perubahan segmental medula spinalis.
Displasia tulang primer dan defek kartilago pada embrio 5-6 minggu.
Defek benih plasma primer
Insersi tendon yang abnormal dan displasia m. peroneus
C. KLASIFIKASI
1. Tipe ekstrinsik/fleksibel
Tipe yang kadang-kadang disebut juga tipe konvensional ini merupakan tipe yang
mudah ditangani dan memberi respon terhadap terapi konservatif. Kaki dalam posisi
equinoverus akan tetap fleksibel dan mudah di koreksi dengan tekanan manuil. Tipe ini
merupakan tipe postural yang dihubungkan dengan postur intrauterin. Kelainan pada
tulang tidak menyeluruh, tidak terdapat pemendekan jaringan lunak yang berat. Tampak
tumit yang normal dan terdapat lipatan kulit pada sisi luar pergelangan kaki.7
14

2. Tipe intrinsik/rigid
Terjadi pada insiden kurang lebih 40% deformitas. Merupakan kasus resisten, kurang
memberi respon terhadap terapi konservatif dan kambuh lagi dengan cepat. Jenis ini
ditandai dengan betis yang kurus, tumit kecil dan tinggi, kaki lebih kaku dan deformitas
yang hanya dapat dikoreksi sebagian atau sedikit dengan deformitas yang hanya dapat
dikoreksi sebagian atau sedikit dengan tekanan manual dan tulang abnormal tampak
waktu dilahirkan. Tampak lipatan kulit di sisi medial kaki.7
D. GAMBARAN KLINIS
Deformitas bentuk kaki dikarakterisasi dengan komponen-komponen anatomis
sebagai berikut: (gambar 7)5,6,7
Adduksi midtarsal
Inversi pada sendi subtalar (varus)
Plantarfleksi sendi talocruralis (equinus)
Kontraksi jaringan di sisi medial kaki
Tendon Achilles memendek
Gastrocnemius kontraktur dan kurang berkembang
Otot-otot evertor sisi lateral tungkai bawah kurang berkembang
Kombinasi deformitas equinus pergelangan kaki dan sendi subtalar, inversi
hindfoot dan adduksi mid-forefoot disebabkan oleh displacement dari sisi medial dan
plantar serta rotasi medial sendi talocalcaneonavicular
Schlicht (1963) melaporkan suatu penelitian CTEV yang dilakukannya pada bayi-bayi
yang lahir mati atau mati segera sesudah lahir. Dilakukan diseksi kaki, yang
semuanya menunjukkan deformitas dengan derajat yang berat. Dia menyatakan
bahwa tulang-tulang mengalami distorsi, khususnya talus, calcaneus, navicularis,
15

cuboid dan metatarsal, tetapi yang paling parah adalah talus. Tidak hanya terjadi
malformasi tulang, tetapi jaringan-jaringan lain yang berhubungan dengannya juga
mengalami distorsi. Pada semua kaki yang didiseksinya, talus memperlihatkan
distorsi facet pada permukaan superior, oleh karena itu tidak pas masuk dalam
lekukan tibia-fibula. Inilah penyebab terpenting persistensi deformitas equinus.
Posisi equinus disebabkan oleh kontraktur dari otot-otot sebagai berikut:
Gastrocnemius
Soleus
Tibialis posterior
Fleksor hallucis longus
Fleksor digitorum longus
Sedangkan posisi varus disebabkan oleh kontraktur pada otot-otot sebagai berikut:
Tibialis anterior dan posterior
Fleksor hallucis longus
Fleksor digitorum longus
Ligamentum deltoid
Otot-otot kecil sisi medial kaki
E. DIAGNOSIS
Kelainan ini mudah didiagnosis, dan biasanya terlihat nyata pada waktu lahir
(early diagnosis after birth). Pada bayi yang normal dengan equinovarus postural, kaki
dapat mengalami dorsifleksi dan eversi hingga jari-jari kaki menyentuh bagian depan
tibia. "Passive manipulation dorsiflexion → Toe touching tibia → normal".
16

Bentuk dari kaki sangat khas. Kaki bagian depan dan tengah inversi dan adduksi. Ibu
jari kaki terlihat relatif memendek. Bagian lateral kaki cembung, bagian medial kaki
cekung dengan alur atau cekungan pada bagian medial plantar kaki. Kaki bagian
belakang equinus. Tumit tertarik dan mengalami inversi, terdapat lipatan kulit
transversal yang dalam pada bagian atas belakang sendi pergelangan kaki. Atrofi otot
betis, betis terlihat tipis, tumit terlihat kecil dan sulit dipalpasi. Pada manipulasi akan
terasa kaki kaku, kaki depan tidak dapat diabduksikan dan dieversikan, kaki belakang
tidak dapat dieversikan dari posisi varus. Kaki yang kaku ini yang membedakan
dengan kaki equinovarus paralisis dan postural atau positional karena posisi intra
uterin yang dapat dengan mudah dikembalikan ke posisi normal. Luas gerak sendi
pergelangan kaki terbatas. Kaki tidak dapat didorsofleksikan ke posisi netral, bila
disorsofleksikan akan menyebabkan terjadinya deformitas rocker-bottom dengan
posisi tumit equinus dan dorsofleksi pada sendi tarsometatarsal. Maleolus lateralis
akan terlambat pada kalkaneus, pada plantar fleksi dan dorsofleksi pergelangan kaki
tidak terjadi pergerakan maleoulus lateralis terlihat tipis dan terdapat penonjolan
korpus talus pada bagian bawahnya. Tulang kuboid mengalami pergeseran ke medial
pada bagian distal anterior tulang kalkaneus. Tulang navicularis mengalami
pergeseran medial, plantar dan terlambat pada maleolus medialis, tidak terdapat celah
antara maleolus medialis dengan tulang navikularis. Sudut aksis bimaleolar menurun
dari normal yaitu 85° menjadi 55° karena adanya perputaran subtalar ke medial.
Terdapat ketidakseimbangan otot-otot tungkai bawah yaitu otot-otot tibialis
anterior dan posterior lebih kuat serta mengalami kontraktur sedangkan otot-otot
peroneal lemah dan memanjang. Otot-otot ekstensor jari kaki normal kekuatannya
tetapi otot-otot fleksor jari kaki memendek. Otot triceps surae mempunyai kekuatan
yang normal.
17

Tulang belakang harus diperiksa untuk melihat kemungkinan adanya spina
bifida. Sendi lain seperti sendi panggul, lutut, siku dan bahu harus diperiksa untuk
melihat adanya subluksasi atau dislokasi. Pmeriksaan penderita harus selengkap
mungkin secara sistematis seperti yang dianjurkan oleh R. Siffert yang dia sebut
sebagai Orthopaedic checklist untuk menyingkirkan malformasi multiple.1
F. PENATALAKSANAAN
Penatalaksanaan harus dimulai sedini mungkin, lebih baik segera sesudah
lahir. Tiga minggu pertama setelah lahir merupakan periode emas/golden period,
sebab jaringan ligamentosa bayi baru lahir masih kendor karena pengaruh hormon
maternal. Fase ini adalah fase kritis dimana jaringan lunak yang kontraktur dapat
dielongasi dengan manipulasi berulang setiap hari. Jika mengharapkan metoda
reduksi tertutup akan mencapai keberhasilan, inilah waktu yang tepat.
Segera setelah bayi lahir, dokter harus menjelaskan kepada orang tuanya
sasaran/goal, sifat dan hakekat CTEV serta tahap-tahap penanganan. Mereka harus
diberi pengertian bahwa pengelolaan CTEV sangat lama, dapat berlanjut dalam
periode bertahun-tahun sampai dewasa, saat maturitas skeletal kaki terjadi, dan
keharusan perawatan serta perhatian yang terus menerus dibutuhkan sepanjang
stadium pertumbuhan tulang.
Penatalaksanaan ada 2 cara, yaitu:2,4
Konservatif
Operatif
18

A. Terapi Konservatif
Tehnik reduksi dengan manipulasi tertutup ini terutama dilakukan untuk tipe
postural, dimana deformitas dapat dikoreksi dengan manipulasi pasif. Program
rehabilitasi medik dibagi dalam beberapa fase, yaitu: 3.4
a. Fisioterapi
1. Mobilisasi/manipulasi pasif
a) Elongasi otot triceps Surae, kapsul posterior dan lig. pergelangan
kaki dan sendi subplantar
Tehnik manipulasi adalah sebagai berikut: terapis memegang
os calcanueus dengan telunjuk dan ibu jari dari 1 tangan, lalu tarik ke
arah distal, sehingga tumit tertarik ke bawah dan terdorong menjauhi
medial maleolus fibular. Dengan tangan yang lain, area
calcaneocuboid didorong ke posisi dorsofleksi sehingga seluruh
bagian kaki inversi ringan. Tidak boleh melakukan stretching bagian
19

tengah kaki dengan memaksakan posisi dorsofleksi forefoot atau
deformitas ‘rocker-bottom’ karena akan menyebabkan ‘patah’ sendi
secara transversal. Posisi yang telah diregang dipertahankan dalam
hitungan 10, kemudian dilepaskan. Stretching pasif ini diulang 20-30
kali tiap sesi.
b) Elongasi otot tibia posterior dan ligamen tibionavicularis
Navicular teregang kearah maleolus medial karena kontraktur
otot tibia posterior dan calcaneonavikular plantaris dan ligamen
tibionavikularis. Untuk melakukan stretching, os calcaneus dipegang
dengan jari telunjuk dan ibu jari 1 tangan dan ditarik ke bawah ke
arah distal, sedangkan tangan yang lain menjepit navikular dengan
jari telunjuk dan ibu jari lalu menarik navikular dan midfoot kearah
distal ibu jari kaki kemudian di abduksi. Korpus os talus dipegang si
tempat pada lekukan pergelangan kaki. Penting untuk tidak
melakukan rotasi lateral di lekukan pergelangan kaki pada talus,
karena dapat menyebabkan ‘patah’ sendi secara horisontal.
c) Elongasi ligamen calcaneoclavicular plantaris (atau pegas) dan
jaringan lunak plantar
Lebih dari 100 tahun yang lalu, Hugh Owens Thomas
menekankan pentingnya jaringan lunak plantar sebagai penghalang
koreksi CTEV. Akan tetapi, baru akhir-akhir ini kita menaruh
perhatian tentang pendapat itu melalui ajaran Wilbur Westin.
Ligamen calcaneoclavicular plantaris harus dielongasi jika tulang
navicular harus berposisi diatas kaput talus. Tehnik stretching
20

manipulatifnya sederhana saja: Dengan 1 tangan, tumit didorong
naik, dan dengan tangan yang lain, midfoot didorong ke arah
dorsofleksi. Ibu jari 1 tangan berada diatas maleolus medialis dan ibu
jari tangan yang lain di atas navicular. Dan, harus dijaga untuk tidak
melakukan tindakan yang menyebabkan rotasi lateral talus pada
lekuk pergelangan kaki. Deformitas iatrogenik berupa celah
horisontal harus dihindari. Seperti pada elongasi triceps surae, tiap
posisi teregang dipertahankan dalam hitungan 10, kemudian
dilepaskan dan diulang 20-30 kali.
Saat manipulasi, semua elemen jaringan lunak yang
kontraktur dielongasi. Hal ini bertentangan dengan tehnik tradisional
Kite yang menyatakan bahwa clubfoot harus dikoreksi bertahap dari
depan ke belakang dan terapis tidak boleh meneruskan tahap
selanjutnya sampai deformitas distalnya telah benar-benar terkoreksi.
Yang pertama dikoreksi adalah varus pada forefoot, kemudian
inversi pada hindfoot dan terakhir equinus pergelangan kaki dan
sendi subtalar. Dia memperingatkan akan bahaya dorsofleksi
prematur sebagai penyebab celah transversal sendi midtarsal yang
berakibat terjadinya kaki ‘rocker-bottom’, yaitu terbaliknya arkus
longitudinal sehingga permukaan plantar berbentuk konveks,
bukannya konkav. Kontroversi yang lain adalah pendapat Lloyd-
Roberts (1971) yang menyatakan koreksi dini ditekankan pada
equinus hindfoot. Sesuai dengannya adalah observasi Attenborough
(1996) bahwa tumit bayi tidak dapat diposisikan valgus atau eversi
jika masih dalam posisi equinus.
21

Yang perlu diperhatikan dalam setiap tindakan mobilisasi
adalah lutut sisi yang sedang dimanipulasi harus dipegang dalam
keadaan fleksi. Hal ini untuk menghindari terjadinya strain
ligamentum medialis pada lutut. Jika kaki dieversi dalam keadaan
tungkai ekstensi, dapat berakibat strain ligamentum medialis lutut
sehingga terjadi deformitas valgus.Resiko mencoba mengkoreksi
terlalu kasar pada elemen plantarfleksi akan cenderung menyebabkan
‘pecahnya’ sendi midtarsal, sehingga kaki akan berbentuk ‘rocker-
shaped’. Pseudokoreksi ini dapat dihindari jika terapis bermaksud
untuk mendapatkan perbaikan sedikit demi sedikit pada hindfoot dan
peningkatan mobilitas daripada terburu-buru mencoba mendapatkan
derajat koreksi yang terlalu besar.
d) Reduksi tertutup dislokasi medial dan plantar sendi
talocalcaneonavikular
Jika jaringan lunak yang kontraktur telah cukup terelongasi, langkah
selanjutnya adalah reduksi tertutup dislokasi medial dan plantar pada
sendi talocalcaneonavikular. Prinsip dasarnya adalah memberikan
traksi kearah distal garis deformitas. Tehnik: genggam hindfoot
dengan 1 tangan, jari telunjuk diatas korpus talus, sebelah anterior
dan distal dari maleolus lateral dan ibu jari tangan yang sama di
anterior maleolus medial, mendorong navikular ke distal. Dengan
tangan yang lain, genggam forefoot dan midfoot dengan ibu jari dan
telunjuk dan berikan traksi longitudinal ke arah distal garis
deformitas, yaitu posisi kaki equinus dan inversi. Manipulasi ini akan
menyebabkan distraksi forefoot dan midfoot dari hindfoot dan
22

elongasi kaki. (Gambar 8F). Selanjutnya reduksi dislokasi
talocalcaneonavikular didapatkan dengan mengabduksikan midfoot,
memindahkan navikular ke lateral dan mendorong ujung anterior
talus ke medial dengan ibujari lainnya. Calcaneus di rotasi ke lateral
os cuboid saat kaki didorsofleksi pada pergelangan kaki dan sendi
subtalarnya. Secara klinis, reduksi menunjukkan kontur eksternal
kaki yang normal pada postur istirahat.
Keberhasilan reduksi dikonfirmasi dengan radiografi posisi
anteropsterior dan lateral yang dibuat dengan posisi standar. Dari
anteroposterior menunjukkan sudut talocalcaneus harus lebih besar
dari 20º dan sudut talo-metatarsal I kurang dari 15º; Dari foto lateral,
sudut talocalcaneus harus 30º-45º. Posisi kaki dan tehnik radiografi
yang benar sangat menentukan.
Metoda apapun yang dipakai, manipulasi pasif selalu dilakukan
terlebih dahulu segera sesudah lahir. Biasanya dilakukan pada hari
ke-2 atau ke-3. Kombinasi manipulasi dengan metoda strapping yang
diulang tiap minggu, biasanya menampakkan hasil dalam 3-6 minggu,
tanpa memandang tipe deformitas mudah atau resisten.
1. Koreksi aktif
Koreksi ini adalah aspek terpenting dalam penatalaksanaan CTEV.
Mobilisasi kaki bayi diikuti dengan usaha menstimulasi eversi dan
dorsofleksi aktif dengan menepuk-nepuk sisi lateral kaki dengan ujung
jari mengarah ke tumit. Jika kaki dapat menapak, bayi mungkin dapat
diberdirikan sebentar dengan berat badan dtumpukan pada kaki yang
sakit dan tumit didorong kebawah, gerakkan dengan lembut dari sisi ke
23

sisi dan kedepan-belakang untuk menstimulasi kontrol muskular aktif
melalui eversi dan dorsofleksi. Pada usia 5 bulan, bayi normal akan
menjangkau dan memegang serta mempermainkan jari-jari kaki dengan
posisi telentang, hal ini harus diupayakan oleh ibu untuk mendapatkan
koreksi aktif. Perlu distimulasi untuk memegang jari-jari sisi lateral
untuk merangsang eversi. Saat mulai duduk pada usia 6-7 bulan, dia
dirangsang bermain dengan kakinya. Menstimulasi sisi anterolateral
kaki akan menrangsang eversi dan dorsofleksi aktif. Banyak metoda
lain yang dapat dipakai untuk menstimulasi gerakan yang diinginkan,
karena itu perlu eksplorasi oleh terapisnya
b. Ortotik prostetik
1. Strapping dengan perban adhesif
Metode ini bertujuan untuk mempertahankan hasil reduksi yang telah
dicapai dan dikonfirmasi dengan radiografi.
Imobilisasi dengan Plaster of Paris cast
Plaster of Paris cast merupakan alat retensi statis.Aplikasi plaster cast
yang benar pada kaki bayi membutuhkan ketrampilan karena harus
dipasang dengan akurat dan detail yang tepat. Dibutuhkan kerjasama 3
orang, yaitu ayah/ibu yang memegang bayi agar diam (karena mungkin
bayi meronta-ronta), seorang asisten yang akan membantu menggulung
lembaran kapas dan ‘plaster of Paris cast’ dan dokter yang memegang
dan membentuk gips. Gips harus terpasang sepanjang tungkai, dari jari
kaki sampai ke lipat paha dengan lutut fleksi 60º-80º untuk mengontrol
tumit dan mencegah gips tergelincir. Tungkai dioles tinktura benzoin
lalu ditutup dengan lembaran kapas selebar 1-1½ inci pada kaki dan
24

tungkai bawah dan selebar 2 inci pada tungkai atas, lutut dan paha.
Lembaran digulung rapi melawan deformitas varus, tidak terlalu kencang
ataupun longgar. Gulungan harus licin dan tidak berkerut. Kemudian
dokter memegang kaki dan pergelangan kaki pada posisi koreksi yang
diinginkan dan asisten menggulungkan plaster of Paris cast, digulung
melawan deformitas varus, dimulai dari sisi lateral kaki, kedorsal,
kemudian keplantar dan kembali ke lateral. Cast diganti dengan interval
2-3 minggu pada bayi baru lahir, karena pertumbuhan kaki yang cepat.
Yang perlu diingat, plaster of Paris cast adalah alat retentif, bukan
korektif.
Tehnik dari Sir Robert Jones (1900) berupa above-knee cast
Gips atas lutut ini menggunakan perban ortopedik adhesif yang diganti
2-3 hari sekali. Pembalutan ini merupakan splint nonrigid dan dinamis
yang mencegah atrofi disuse dan mendukung berfungsinya otot peroneus
dan dorsofleksor pergelangan kaki pada minggu-minggu pertama setelah
lahir.
Tehnik: pertama, sepanjang ekstremitas dicuci dengan air dan sabun,
kemudian dibersihkan dan dikeringkan dengan alkohol. Tinktura benzoin
dioleskan pada kaki dan seluruh tungkai (antara lutut dan maleolus) dan
paha bagian distal yaitu 3-5cm diatas lutut. Tinktura ini akan melindungi
kulit dan memperbaiki pelekatan strapping. Kemudian kain perban
adhesif selebar 3-5cm digulung dengan lembut melingkar, tetapi tidak
semuanya, sekitar kaki dengan tepi 1cm dari garis tengah dorsum kaki.
Strapping sirkumferensial (Jones) relatif aman pada bayi usia 1-3
minggu. Penting untuk menempatkan tepi distal dari lembaran kapas
25

(dan strap adhesif) di ujung basis jari kaki untuk menopang kaput
metatarsal dan secara dinamis meregang forefoot keluar dari posisi
equinus.
Tehnik strapping dan gesper
Tehnik ini untuk memegang kaki dalam posisi terkoreksi, derajat
koreksi dapat diubah dengan menyesuaikan tarikan pada gesper. Jika
kaki dapat dipertahankan dalam posisi eversi, akan memfasilitasi
kontraksi aktif otot evertor dan dorsofleksor tiap kali bayi melakukan
gerakan ekstensi tungkai.
Metoda pemasangan (gambar 10): Strap dipotong menjadi beberapa
bagian, gesper dipasang, lalu strap dijahit. Sebelum memasang strap,
terapis memobilisasi kaki. Tinktura benzoin dioleskan ke kulit dengan
kapas dan dibiarkan mengering sebelum strapping.
2. Splinting
Split logam tipe Dennis Browne
Splint ini terdiri dari 2 potong aluminium yang dibentuk menjadi foot
plate dengan bagian memanjang pada sisi lateral tungkai. Foot plate
harus sesuai ukuran kaki bayi, jika terlalu lebar, strapping tidak dapat
mengontrol adduksi. Sedangkan pemanjangan bagian lateral harus
setinggi tungkai bawah. Jika terlalu pendek akan mengurangi kekuatan
yang dibutuhkan untuk mempertahankan posisi eversi.
Pada deformitas unilateral, kaki yang normalpun harus dipasang splint.
Splint kanan dan kiri disatukan dengan palang melintang yang dapat
digerakkan. Palang ini ditempelkan pada foot plate dengan sekrup kupu-
26

kupu . Palang dapat ditekuk membentuk sudut kecil dan jika tungkai dan
kaki dalam posisi rotasi eksterna maka foot plate akan memfasilitasi
eversi dan dorsofleksi saat tungkai bayi ekstensi.
Posterior plaster splint
Plaster splint berbantalan dibuat untuk menahan kaki pada midposisi
atau inversi dan dorsofleksi. Tipe ini tidak berguna untuk CTEV berat
karena ada tendensi relaps, meskipun dengan pembalutan, tidak dapat
mengontrol tendensi kembali ke posisi equinovarus. Akan tetapi, splint
ini berguna pada deformitas postural yang ringan untuk mempertahankan
koreksi sampai anak dapat mengkoreksi sendiri, pada bayi dengan
meningocele dimana tungkai flaksid, keseimbangan otot tidak ada, dan
koreksi harus dipertahankan sampai operasi stabilisasi untuk koreksi
dapat dilakukan.
Dennis Browne night splint
Splint ini kadang-kadang diberikan sebagai alat untuk
mempertahankan koreksi yang telah didapatkan dari strapping atau splint
logam Denis Browne. Terdiri dari sepasang sepatu boot yang
ditempelkan pada piringan logam diatas palang melintang
Prinsipnya mirip dengan splint logam. Tungkai dipegang pada posisi
rotasi eksternal dan kaki dieversi dan dorsofleksikan. Splint ini dipakai
siang dan malam atau saat malam hari hanya jika anak berjalan.
Bell-Grice splint
Konstruksi splint ini mirip dengan Dennis Browne tetapi memiliki
keunggulan tertentu, yaitu logam pada foot plate terbentuk dengan baik
27

sehingga pembalutan dengan lembaran kapas tidak diperlukan dan
‘boating’ pada kaki tidak terjadi. Keuntungan lain adalah tidak ada
pemanjangan metal ke lateral untuk menekan sisi luar tungkai, sehingga
kelemahan otot, antara lain evertor dapat dihindari.
Foot plate dan splint terpisah dari palang melintang dan dilapisi dengan
lapisan adhesif lipis lembaran kapas, 2 potong strap selebar 2cm
dipasang pada sol/bagian belakang sepatu diatas sekrup, 1 diantaranya
lewat dari dalam keluar melalui sisi bawah, yang lain dari dalam keluar
melalui sisi atas. Seorang asisten menahan ekstremitas dan kaki bayi
diletakkan pada bagian sol. Lalu dilakukan strapping, melewati dorsum
pedis keatas dan kebawah melewati pergelangan kaki. Potongan strap
yang kedua dipasang dengan cara yang sama. Potongan ketigadigunakan
untuk menahan tumit pada foot plate lalu dikencangkan dengan sepotong
strap yang melimgkari ekstremitas. Kaki akan berposisi eversi maksimal
dan terkunci pada foot plate.
B. Terapi Operatif
Indikasi pemilihan pelaksanaan terapi operatif adalah adanya komplikasi yang
terjadi setelah terapi konservatif. Pada kasus resisten, terapi operatif paling baik
dilakukan pada usia 3-6 minggu, ketika tidak tampak adanya perbaikan yang
signifikan setelah menjalani terapi konservatif yang teratur.
Ada beberapa macam prosedur operatif untuk koreksi CTEV. Pemilihan prosedur
dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
Usia anak
Derajat rigiditas
28

Deformitas yang ditemukan
Komplikasi yang didapat dari penanganan sebelumnya
Prosedur terapi operatif adalah:
1. Koreksi jaringan lunak
Koreksi jaringan lunak dilakukan pada bayi dan anak dibawah 5 tahun.
Pada usia ini, biasanya belum ada deformitas pada tulang-tulang kaki, bila
dilakukan operasi pada tulang dikhawatirkan malah merusak tulang dan sendi
kartilago anak yang masih rentan.
Koreksi dilakukan pada:
1. otot dan tendon
Achilles : tehnik pemanjangan tendo (Z-lengthening)
Tibia posterior: tehnik pemanjangan tendo atau transfer
Abduktor hallucis longus: tehnik reseksi atai eksisi
Fleksor hallucis longus dan fleksor digitorum longus: tehnik pemanjangan
atau reseksi muskulotendineus
Fleksor digitorum brevis
2. Kapsul dan ligamen
Talonavicular
Subtalar
Sendi calcaneocuboid
Kapsul pergelangan kaki, antara lain bagian dari lig. deltoid
Ligamen yang kontraktur pada sisi posterolateral pergelangan kaki dan
sendi subtalar:
◦ Lig. calcaneofibular
29

◦ Lig. Talofibular posterior
◦ Retinakulum peroneal superior
Ligamen interoseus talocalcaneal
2. Koreksi jaringan keras
Operasi pada tulang atau osteotomi dilakukan setelah usia anak 5-10
tahun. Karena pada usia ini biasanya telah terjadi deformitas struktur tulang
dan koreksi yang diharapkan tidak mungkin berhasil tanpa pembenahan
tulang. Tindakan berupa:
1. Osteotomi calcaneus untuk koreksi inversi
2. Wedge reseksi sendi calcaneocuboid
3. Osteotomi cuboid
4. Osteotomi cuneiformis untuk koreksi adduksi yang berlebihan
5. Osteotomi tibia dan fibula, jika torsi tibia berlebihan (jarang terjadi)
Tindakan pada anak dengan usia lebih tua, lebih dari 10 tahun, biasanya:
1. Rekonstuksi tarsal, termasuk triple arthrodesis. Dilakukan pada kaki yang
rigid dan seringkali diserta nyeri serta tidak berespon pada gips serial atau
prosedur operasi yang lain.
2. Osteotomi femur
G. PROGNOSIS
Bila terapi dimulai sejak lahir, deformitas sebagian besar selalu dapat diperbaiki.
Walaupun demikian, keadaan ini tidak dapat sembuh sempurna dan sering kambuh,
30

sehubungan dengan tipenya, terutama pada bayi yang disertai dengan kelumpuhan otot
yang nyata atau disertai penyakit neuromuskular.8
Prognosis ditentukan oleh beberapa faktor utama dan penunjang, antara lain:
1. Deformitas yang terjadi
2. Kapan mulai dilakukan.
Penatalaksanaan: semakin dini dilakukan semakin baik
3. Orang tua penderita.
Peran orang tua sangat penting. Faktor-faktor yang diperlukan adalah faktor kesabaran,
ketelatenan dan pengertian.
BAB III
KESIMPULAN
31

Congenital Talipes Equinovarus (Clubfoot) adalah salah satu kelainan bawaan
pada kaki yang terpenting. Kelainan ini mudah didiagnosa tapi sulit diterapi secara
sempurna walaupun oleh seorang yang sangat ahli. Kelainan yang terjadi pada
Clubfoot adalah : equinus pada tumit, seluruh hindfoot varus, serta midfoot dan
forefoot aduksi dan supinasi.
Derajat kelainan mulai dari ringan, sedang atau berat yang dilihat dari
rigiditasnya atau resistensinya, dan dari penampilannya.
Pengenalan dan penanganan secara dini pada clubfoot sangat penting dimana
“Golden Period” untuk terapi adalah tiga minggu setelah lahir, karena pada umur
kurang dari tiga minggu ligamen-ligamen pada kaki masih lentur sehingga masih
dapat dimanipulasi.
DAFTAR PUSTAKA
32

1. Schwarts SI. Principles of Surgery. Singapore: Mc Graw Hill International
Book Company; 1984: 1888-1890.
2. Patel, M. 2007. Clubfoot. www.emedicine.com [29 juli 2008]
3. Shepherd Roberta B. Physiotherapy in Paediatrics. London: William
Heinemann Medical Books Limited, 1974: 4-5.
4. Cailliet Rene. Foot and Ankle Pain. 12th ed. Philadelphia: F.A. Davis
Company, 1980: 1-21
5. Ferner H, J. Staubesand. The Sobotta Atlas of Human Anatomy, Vol II, Ed.
Bahasa Indonesia. Jakarta: EGC Penerbit Buku Kedokteran, 1985: 346.
6. Munandar A. Iktisar Anatomi Alat Gerak dan Ilmu Gerak, Ed. 1. Jakarta: EGC
Penerbit Buku Kedokteran, 1979:142-162
7. Crenshaw AH. Campbell‘s Operative Orthopaedics, 7th ed. Missouri: Mosby
Co., 1987: 288-292.
8. Apley E. Graham, Solomon Louis. Apley’s System of Orthopaedics and
Fractures. 7th ed. Ed Bahasa Indonesia, Jakarta: Widya Medika, 1993:200-202.
33