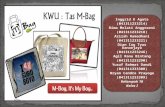Fix
-
Upload
muhammad-kholid-firdaus -
Category
Documents
-
view
216 -
download
2
description
Transcript of Fix

B. Antihistamin1. Definisi
Antihistamin adalah zat zat yang dapat mengurangi atau menghalagi efek histamin terhadap tubuh dengan jalan mengeblok reseptor histamin. Anti histamin adalah zat yang digunakan untuk mencegah atau menghambat kerja histamin pada reseptornya. Histamin sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu histos yang berarti jaringan.
Histamin adalah autakoid yang berperan penting pada aktivitas organ tubuh baik pada proses yang fisiologis maupun patologis. Histamin bekerja dengan menduduki reseptor tertentu pada sel yang terdapat pada permukaan memberan. Terdapat 3 jenis reseptor histamin H1, H2, H3; reseptor tersebut termasuk golongan reseptor yang berpasangan dengan protein G. Pada otak, reseptor H1 dan H2 terletak pada membran pascasinaptik, sedangkan reseptor H2 terutama prasinaptik.
Secara farmakologis reseptor histamin dapat di bagi dalam 3 tipe yaitu histamin 1 (H1), histamin 2 (H2), dan histamin 3 (H3). Peran reseptor tersebut berbeda – beda. Reseptor H1 terdapat di kulit dan otak. Rangsangan pada reseptor H1 menyebabkan kontraksi otot polos, vasodilatasi, peningkatan permeabilitas kapiler, sekresi mucus serta menimbulkan rasa gatal. Reseptor H2 terutama menyebabkan rangsangan sekresi asam lambung dan beberapa hormon. Reseptor H3 terdapat di otak dan bertanggung jawab sebagai autoregulasi pelepasan histamin.
Aktivasi reseptor H1, yang terdapat pada endotel dan sel otot polos, menyebabkan kontraksi otot polos, meningkatkan permabilitas pembuluh darah, dan sekresi mukus. Sebagian dari efek tersebut mungkin diperantarai oleh peningkatan cyclic guanosine monophosphate di dalam sel. Histamin juga berperan sebagai neurotransmiter dalam susunan saraf pusat.
Reseptor H2 didapatkan pada mukosa lambung, sel otot jantung, dan beberapa sel imun. Aktivasi reseptor H2 terutama menyebabkan sekresi asam lambung. Selain itu juga berperan dalam menyebabkan sekresi asam lambung. Selain itu juga berperan dalam menyebabkan vasodilatasi dan flushing. Histamin menstimulasi sekresi asam lambung, meningkatkan kadar cAMP, dan menurunkan kadar cGMP, sedangkan anithistamin H2 menghambat efek tersebut. Pada otot polos bronkus, aktivasi reseptor H1 oleh histamin menyebabkan bronkokonstriksi, sedangkan aktivasi reseptor H2 oleh agonis reseptor H2 akan menyebabkan relaksasi.
Reseptor H3 berfungsi sebagai penghambat umpan balik pada berbagai sistem organ. Aktivasi reseptor H3 yang didapatkan di beberapa daerah di otak mengurangi pelepasan transmiter baik histamin maupun norepinefrin, serotononin, dan asetilkolin. Meskipun agonis reseptor H3 berpotensi untuk digunakan antara lain sebagai gastroprotektif, dan antagonis reseptor H3 antara lain berpotensi untuk digunakan sebagai antiobesitas, sampai saat ini belum ada agonis maupun anatagonis reseptor H3 yang diizinkan digunakan di klinik.
2. Klasifikasia. Antihistamin Penghambat Reseptor H1 (AH1)

Antihistamin H1 merupakan salah satu obat terbanyak dan terluas digunakan di seluruh dunia. Fakta ini membuat perkembangan sekecil apapun yang berkenaan dengan obat ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Semisal perubahan dalam penggolongan antihistamin H1. Dulu antihistamin H1 dikenal sebagai antagonis reseptor histamin H1. Namun baru-baru ini seiring perkembangan ilmu farmakologi molekular, antihistamin H1 lebih digolongkan sebagai inverse agonist ketimbang antagonis reseptor histamin H1.
Suatu obat disebut sebagai inverse agonist bila terikat dengan sisi reseptor yang sama dengan agonis, namun memberikan efek berlawanan. Jadi, obat ini memiliki aktivitas intrinsik (efikasi negatif) tanpa bertindak sebagai suatu ligan. Sedangkan suatu antagonis bekerja dengan bertindak sebagai ligan ynag mengikat reseptor atau menghentikan kaskade pada sisi yang ditempati agonis. Beda dengan inverse agonist, suatu antagonis sama sekali tidak berefek atau tidak mempunyai aktivitas intrinsik.
Sebelumnya antihistamin dikelompokkan menjadi 6 grup berdasarkan struktur kimia, yakni etanolamin, etilendiamin, alkilamin, piperazin, piperidin, dan fenotiazin. Penemuan antihistamin baru yang ternyata kurang bersifat sedatif, akhirnya menggeser popularitas penggolongan ini. Antihistamin kemudian lebih dikenal denagn penggolongan baru atas dasar efek sedatif yang ditimbulkan, yakni generasi pertama, kedua, dan ketiga.. Generasi pertama dan kedua berbeda dalam dua hal yang segnifikan. Generasi pertama lebih menyebabkan sedasi dan menimbulkan efek antikolinergenik yang lebih nyata. Hal ini dikarenakan generasi pertama kurang selektif dan mampu berpenetrasi pada sistem syaraf pusat (SSP) lebih besar dibanding generasi kedua. Sementara itu, generasi kedua lebih banyak dan lebih banyak terikat dengan protein plasma, sehingga mengurangi kemampuannya melintasi otak. Sedangkan generasi ketiga merupakan derivat dari generasi kedua, berupa metabolit (desloratadine dan fexofenadine) dan enansiomer (levocetirizine). Pencarian generasi ketiga ini dimaksudkan untuk memproleh profil antihistamin yang lebih baik dengan efikasi tinggi serta efek samping lebih minimal.
1) Klasifikasi atau Penggolongan antihistamin 1 (AH1)a) Antihistamin generasi pertama
AH1 efektif untuk mengatasi urtikaria akut, sedangkan pada urtikaria kronik hasilnya kurang baik. Mekanisme kerja antihistamin dalam menghilangkan gejala-gejala alergi berlangsung melalui kompetisi dalam berikatan dengan reseptor H1 di organ sasaran. Histamin yang kadarnya tinggi akan memunculkan lebih banyak reseptor H1. Antihistamin tersebut digolongkan dalam antihistamin generasi pertama.
Pada umumnya obat antihistamin generasi pertama ini mempunyai efektifitas yang serupa bila digunakan menurut dosis yang dianjurkan dan dapat dibedakan satu sama lain menurut gambaran efek sampingnya. Namun, efek yang tidak diinginkan obat ini adalah menimbulkan rasa mengantuk sehingga mengganggu aktifitas dalam pekerjaan.
Efek sedatif ini diakibatkan oleh karena antihistamin generasi pertama ini memiliki sifat lipofilik yang dapat menembus sawar darah otak sehingga dapat menempel pada reseptor H1 di sel-sel otak. Dengan tiadanya histamin yang menempel pada reseptor H1 sel otak, kewaspadaan menurun dan timbul rasa

mengantukSelain itu, efek sedatif diperberat pada pemakaian alkohol dan obat antidepresan. Di samping itu, beberapa antihistamin mempunyai efek samping antikolinergik seperti mulut menjadi kering, dilatasi pupil, penglihatan berkabut, retensi urin, konstipasi dan impotensia.Yang termasuk golongan ini adalah:
Alkilamin (propilamin) : bromfeniramin maleat, klorfeniramin maleat dan tanat, deksbromfeniramin maleat, deksklorfeniramin maleat, dimentinden maleat, tripolidin hidroklorida, feniramin maleat/pirilamin maleat.
Etanolamin (Aminoalkil eter) :karbioksamin maleat, difenhidramin sitrat dan hidroklorida, doksilamin suksinat, embramin hidroklorida, mefenhidramin metilsulfat, trimetobenzamin sitrat, dimenhidrinat, klemastin fumarat.
Etilendiamin : mepiramin maleat, pirilamin maleat, tripenelamin sitrat dan hidroklorida, antazolin fosfat.
Fenotiazin : dimetotiazin mesilat, mekuitazin, metdilazin dan metdilazin hidroklrida, prometazin hidroklorida dan teoklat, trieprazin tartrat.
Piperidin : azatadin maleat, siproheptadin hidroklorida, difenilpralin hidroklorida, fenindamin tartrat.
Piperazin : hidroksizin hidroklorida dan pamoat.4
b) Antihistamin generasi keduaAntihistamin generasi kedua mempunyai efektifitas antialergi seperti
generasi pertama, memiliki sifat lipofilik yang lebih rendah sulit menembus sawar darah otak. Reseptor H1 sel otak tetap diisi histamin, sehingga efek samping yang ditimbulkan agak kurang tanpa efek mengantuk. Obat ini ditoleransi sangat baik, dapat diberikan dengan dosis yang tinggi untuk meringankan gejala alergi sepanjang hari, terutama untuk penderita alergi yang tergantung pada musim. Obat ini juga dapat dipakai untuk pengobatan jangka panjang pada penyakit kronis seperti urtikaria dan asma bronkial. Peranan histamin pada asma masih belum sepenuhnya diketahui. Pada dosis yang dapat mencegah bronkokonstriksi karena histamin, antihistamin dapat meredakan gejala ringan asma kronik dan gejala-gejala akibat menghirup alergen pada penderita dengan hiperreaktif bronkus. Namun, pada umumnya mempunyai efek terbatas dan terutama untuk reaksi cepat dibanding dengan reaksi lambat, sehingga antihistamin generasi kedua diragukan untuk terapi asma kronik. Yang termasuk golongan ini adalah:
Akrivastin Astemizole Cetirizin Loratadin Mizolastin Terfenadin Ebastin

c) Antihistamin generasi ketigaAntihistamin generasi ketiga yaitu feksofenadin, norastemizole dan deskarboetoksi loratadin (DCL), ketiganya adalah merupakan metabolit antihistamin generasi kedua. Tujuan mengembangkan antihistamin generasi ketiga adalah untuk menyederhanakan farmakokinetik dan metabolismenya, serta menghindari efek samping yang berkaitan dengan obat sebelumnya.Yang termasuk golongan ini adalah:
Levocetirizin Desloratadin Fexofenadin
b)
3. Mekanisme Kerja
H2
Reseptor histamin H2 berperan dalam efek histamin terhadap sekresi cairan lambung,
perangsangan jantung. Beberapa jaringan otot polos pembuluh darah mempunyai
kedua reseptor yaitu H1 dan H2.
Sejak tahun 1978 di Amerika Serikat telah diteliti peran potensial H2cemitidine untuk
penyakit kulit. Pada tahun 1983, ranitidine ditemukan pula sebagai antihistamin
H2. Baik simetidine dan ratidine diberikan dalam bentuk oral untuk mengobati
penyakit kulit
1) Struktur
Antihistamin H2 secara struktur hampir mirip dengan histamin. Simetidin
mengandung komponen imidazole, dan ranitidin mengandung komponen
aminomethylfuran moiety.
2) Farmakodinamik
Simetidine dan ranitidine menghambat reseptor H2 secara selektif dan reversibel.
Perangsangan reseptor H2 akan merangsang sekresi cairan lambung, sehingga
pada pemberian simetidin atau ranitidin sekresi cairan lambung dihambat.

Pengaruh fisiologi simetidin dan ranitidin terhadap reseptor H2 lainnya, tidak
begitu penting. Walau tidak lengkap simetidin dan renitidin dapat menghambat
sekresi cairan lambung akibat perangsangan obat muskarinik atau gastrin.
Semitisin dan ranitidin mengurangi volume dan kadar ion hidrogen cairan
lambung. Penurunan sekresi asam lambung mengakibatkan perubahan pepsinogen
menjadi pepsin juga menurun.
3) Farmakokinetik
Bioavaibilitas oral simetidin sekitar 70%, sama dengan setelah pemberian IV atau
IM. Absorpsi simetidin diperlambat oleh makanan. Absorpsi terjadi pada menit ke
60-90. Masa paruh eliminasi sekitar 2jam. Bioavaibilitas ranitidin yang diberikan
secara oral sekitar 50% dan meningkat pada pasien penyakit hati. Pada pasien
penyakit hati masa paruh ranitidin juga memanjang meskipun tidak sebesar pada
gagal ginjal. Kadar puncak plasma dicapai dalam 1-3 jam setelah pengguanaan
150 mg ranitidin secara oral, dan yang terikat protein plasma hanya 15%.Sekitar
70% dari ranitidin yang diberikan IV dan 30% dari yang diberikan secara oral
diekskresi dalam urin.
4) Mekanisme aksi
Walaupun simetidin dan ranitidin berfungsi sama yaitu menghambat reseptor H2,
namun ranitidin lebih poten. Simetidin juga menghambat histamin N-methyl
transferase, suatu enzim yang berperan dalam degrasi histamin. Tidak seperti
ranitidin, simetidin menunjukkan aktivitas antiandrogen, suatu efek yang
diketahui tidak berhubungan dengan kemampuan menghambat raseptor
H2. Simetidin tampak meningkatkan sistem imun dengan menghambat aktivitas
sel T supresor. Hal ini disebabkan oleh blokade resptor H2 yang dapat dilihat dari
supresor limfosit T. Imunitas humoral dan sel dapat dipengaruhi.
5) Indikasi
Simetidin dan ranitidin diindikasikan untuk tukak peptik. Antihistamin H2 sama
efektif dengan pengobatan itensif dengan antasid untuk penyembuhan awal tukak

lambung dan duodenum. Antihistamin H2 juga bermanfaat untuk hipersekresi
asam lambung pada sindrom Zollinger-Ellison.
Penggunaan antihistamin H2 dalam bidang dermatologi seringkali digunakan
ranitidin atau simetidin untuk pengobatan gejala dari mastocytosis sistematik,
seperti urtikaria dan pruritus. Pada beberapa pasien pengobatan digunakan dosis
tinggi.
6) Kontraindikasi
a) Kehamilan
b) Ibu menyusui
7) Efek samping
Insiden efek samping kedua obat ini rendah dan umumnya berhubungan dengan
pemhambatan terhadap reseptor H2, beberapa efek samping lain tidak
berhubungan dengan penghambatan reseptor. Efek samping ini antara lain : nyeri
kepala, pusing, malaise, myalgia, mual, diare, konstipasi, ruam kulit, pruritus,
kehilangan libido, dan impoten.
Simetidin mengikat reseptor androgen dengan akibat disfungsi seksual dan
ginekomastia. Ranitidin tidak berefek antiandrogenik sehingga penggantian terapi
dengan ranitidin mungkin akan menghilangkan impotensi dan ginekomastia
akibat simetidin. Simetidin IV akan merangsang sekresi prolaktin, tetapi hal ini
pernah pula dilaporkan setelah pemberian simetidin kronik secara oral. Pengaruh
ranitidin terhadap peninggian prolaktin ini kecil.
8) Interaksi Obat
Antasid dan metoklopramid mengurangi biovailabilitas oral simetidin sebanyak
20-30%. Ketakonazol harus diberikan 2jam sebelum pemberian simetidin karena
absorpsi ketakonazol berkurang sekitar 50% bila diberikan bersama simetidin.
Selain itu ketakonazol membutuhkan pH lebih tinggi yang terjadi pada pasien
yang juga mendapat AH2.
Simetidin terikat sitokrom P-450 sehingga menurunkan aktivitas enzim mikrosom
hati, jadi obat lain akan terakumulasi bila diberikan bersama simetidin. Obat yang
metabolismenya dipengaruhi simetidin adalah arfarin, karbamazepin, diazepam,
propranolol, metaprolol dan imipramin.

Ranitidin jarang berinteraksi dengan obat lain dibandingkan dengan simetidin
akan tetapi makin banyak obat dilaporkan berinteaksi dengan ranitidin yaitu
nifedifin warfarin, teofilin, dan metaprolol. Ranitidin dapat menghambat absorbsi
diazepam dan dapat mengurangi kadar plasmanya sejumlah 25%. Obat-obat ini
diberikan dengan selang waktu minimal 1 jam sam a dengan penggunaan
ranitidin bersama abtasid atau antikolinergik.
Simetidin dan ranitidin cenderung menurunkan aliran darah hati sehingga akan
memperlambat bersihan obat lain. Simetidin dapata menghambat alkohol
dehidrigenase dalam mukosa lambung dan menyebabkan peningkatan kadar
alkohol serum. Simetidin juga mengganggu disposisi dan meningkatkan kadar
lidokoin serta meningkatkan antagonis kalsium dalam serum. Simetidin dapat
menyebabkan berbagai gangguan SSP terutama pada pasien usia lanjut atau
dengan penyakit hati atau ginjal. Gejala ganggua slurredspeech, somnolen, letargi,
gelisah, bingung, disorentasi, agitasi, halusinasi, dan kejang. Gejala seperti
demensia dapat timbul pada penggunaan simetidin bersama obat psikotropik atau
sebagai efek samping simetidin. Ranitidin menyebabkan gangguan SSP ringan
karena sukarnya melewati sawar darah otak.
Efek samping simetidin yang jarang terjadi adalah trombositopenia,
granulositopenia, toksisitas terhadap ginajal atau hati. Pemberian simetidin dan
ranitidin IV sesekali menyebabkan bradikardi dan efek kardiotoksik lain.
FAMOTIDIN
Farmakodinamik.
Seperti halnya dengan simetidin dan ranitidin. Famotidin
merupakan AH2 sehingga dapat menghambat sekresi asam lambung
pada keadaan basal, malam dan akibat distimulasi oleh pentagastrin.

Famotidin tiga kali lebih potan dari pada renitidin dan 20 kali lebih poten
daripada simetidin.
Farmakokinetik.
Femotidin mencapai kadar puncak di plasma kira – kira dalam 2
jam setelah penggunaan secara oral, masa paruh eliminasi 3-8 jam dan
viovailabilitas 40-50%. Metabolit utama adalah femotidin-S- oksida.
Setelah dosis oral tunggal, sekitar 25% dari dosis ditemukan dalam
bentuk asal di urin. Pada pasien gagal ginjal berat masa paruh eliminasi
dapat melebihi 20 jam.
Indikasi
Efektivitas obat ini untuk tukak duodenum dan tukak lambung setelah 8 minggu
pengobatan sebanding dengan ranitidin dan simetidin. Pada penelitian selama 6
bula famotidin juga mengurangi kekambuhan tukak duodenum yang secara klinis
bermakna. Famotidin kira-kira sama efektif dengan AH2 lainnya pada pasien
sindrom Zollinger-Ellison meskipun untuk keadaan ini omeprazol merupakan
obat terpilih. Efektivitas famotidin untuk profilaksis tukak lambung, refluks
esofagitis dan pencegahan tukak stres pada saat ini sedang diteliti.
Efek samping.
Efek samping femotidin biasanya ringan dan jarang terjadi, misalnya sakit
kepala, pusing, konstipasi dan diare. Seperti halnya dengan ranitidin
famotidin nampaknya lebih baik dari simetidin karena tidak menimbulkan
efek antiandrogenik. Famotidin harus digunakan hati-hati pada ibu menyusui
karena obat ini belum diketahui apakah obat ini diekskresi kedalam air susu ibu.

Interaksi obat
Fenotidin tidak mengganggu oksidasi diazepam, teofilin, warfarin,
atau fenitoin di hati. Ketakonazot membutuhkan pH asam untuk bekerja
sehingga kurang efektif bila diberikan bersama AH2.
NIZATIDIN
Farmakodinamik.
Potensi nizatidin dalam menghambat sekresi asam lambung
kurang. Lebih sama dengan ranitidin.
Farmakokinetik
Biovailabilitas oral nizatidin lebih dari 90% dan tidak di pengaruhi
oleh makanan atau antikolinergik. Kirens menurun pada pasien uremik
dan usia lanjut.
Kadar puncak dalam serum setelah pemberian oral dicapai dalam 1 jam,
masa paruh plasma sekitar 11/2 jam dan lama kerja sampai dengan 10 jam.
Nizatidin di sekresi terutama melalui ginjal 90% dari dosis yang
digunakan ditemukan di urin dalam 16 jam.
Indikasi
Efektvitas untuk pengobatan gangguan asam lambung sebanding dengan ranitidin
dan simetidin. Dengan pemberian satu atau dua kali sehari biasanya dapat
menyembuhkan tukak duodeni dalam 8 minggu dan dengan pemberian satu kali
sehari nizatidin mencegah kekambuhan. Pada refluks esofagitis, sindrom
Zollinger-Ellison dan gangguan asam lambung lainnyan nizatidin siperkirakan
sama efektif dengan ranitidin meskipun masih diperlukan pembuktian lanjut.

Efek samping.
Nizatidin umumnya jarang menimbulkan efek samping. Efek
samping ringan saluran cerna dapat terjadi. Peningkatan kadar asam urat
dan transminase serum ditemukan pada beberapa pasien yang
nampaknya tidak menimbulkan gejala klinik yang bermakna. Seperti
halnya dengan AH2 lainnya, potensi nizatidin untuk menimbulkan
hepatotoksisitas rendah . nizatidin tidak mempunyai efek antiandrogenik.
Nizatidin dapat menghambat alcohol dehidrogenase pada mukosa
lambung dan menyebabkan kadar alcohol yang lebih tinggi dalam kadar
serum. Nizatidin tidak menghambat system P450. Pada sukarelawan
sehat tidak dilaporkan terjadinya interkasi obat bila nizatidin diberikan
bersama teofilin, lidokain, warfarin, klordiazepoksid, diazepam, atau
lorazepam. Penggunanan bersama antacid tidak menurunkan absorbs
nizatidin secara bermakna. Ketokonazol yang membutuhkan pH asam
menjadi kurang efektif bila pH lambung lebih tinggi pada pasien yang
mendapat AH2.