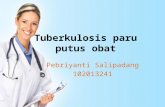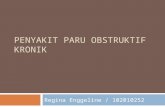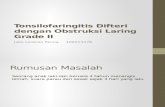Blok 18 Difteri
-
Upload
alfrida-ade-bunapa -
Category
Documents
-
view
36 -
download
1
description
Transcript of Blok 18 Difteri

Difteri pada Anak dengan Riwayat Imunisasi Tidak Lengkap
Alfrida Ade Bunapa/102011137
Email:[email protected]
Fakultas Kedokteran Universitas Krida Wacana
Jl. Arjuna Utara No.6, Jakarta 11510.
Pendahuluan
Difteria adalah suatu penyakit infeksi akut yang terjadi secara local pada membrane
mukosa atau kulit yang disebabkan oleh basil gram positif, Corynebacterium diphtheriae.
Infeksi ini biasanya terjadi di saluran napas bagian atas yang ditandai oleh terbentuknya
pseudomembran pada tempat infeksi dan diikuti oleh gejala-gejala umum yang ditimbulkan
oleh eksotoksin yang diproduksi oleh bakteri ini.
Manifestasi klinis dari difteria tergantung dari lokasi infeksi, imunitas penderita, dan
ada/tidaknya toksin difteri yang beredar di dalam sirkulasi darah. Gejalanya mulai dari yang
paling ringan seperti gejala influenza biasa, sampai kepada yang paling berat yang
menimbulkan obstruksi saluran napas yang tidak jarang menimbulkan kematian.
Anamnesis
Keluhan Sesak Napas
Riwayat penyakit sekarang
Sudah berapa lama sesak napas?
Bagaimana awalnya: mendadak atau bertahap? Apa yang sedang dilakukan pasien
saat awal gejala: berbaring, berlari, berjalan, dan sebagainya?
Apakah sesak napas semakin memburuk?
Apakah yang memicunya dan apakah yang meredakannya? (postur, obat, atau
oksigen)
Adakah ortopnea?
Adakah gejala penyerta? (nyeri dada, batuk, palpitasi, hemoptisis, dan mengi)3
Riwayat penyakit dahulu
1

Adakah episode serupa sebelumnya?
Adakah riwayat penyakit kardiovaskular atau pernapasan? (khususnya gagal jantung,
asma, PPOK, atau emboli paru)
Adakah sebab potensial untuk asidosis? (misalnya ketoasidosis diabetikum, gagal
jantung)
Adakah alergi?
Riwayat pengobatan
Terapi apa yang pernah dilakukan pasien? Adakah pajanan pada obat dengan efek
samping pernapasan (misalnya amiodaron dan fibrosis paru)?
Apakah pasien menggunakan oksigen/nebiliser/inhaler di rumah?
Riwayat social
Bagaimana pengaruh sesak pada aktivitas?
Pernahkah ada pajanan di tempat tinggal?
Keluhan batuk
Sudah berapa lama?3
Akut (≤ 3 minggu)
Penyebabnya antara lain adalah infeksi saluran napas atas (misalnya
influenza), pneumonia, oedem paru, eksaserbasi PPOK, rhinitis alergika, dan
pertusis.
Subakut (3-8 minggu)
Penyebab di antaranya: batuk pasca infeksi, sinusitis, dan asma.
Kronis (≥ 8 minggu)
Penyebab di antaranya: postnasal drip, asma, refluks gastroesofagus, kanker
paru, bronkiektasis, TB, dan PPOK.
Apakah ada sputum? Apa warna dan berapa banyak sputum?
Adakah darah?
Apakah disertai gejala yang menunjukkan penyakit serius? (hemoptisis, sesak napas,
nyeri dada, penurunan berat badan)
Adakah demam, takikardi, takipnea?
Adakah riwayat penyakit pernapasan kronis?
Adakah tanda-tanda sinusitis (missal nyeri gigi maksilaris, secret hidung purulen, atau
nyeri wajah) ?
2

Apakah pasien terpajan penyebab infeksi khusus (misalnya pertusis, allergen, atau
obat)
Adakah anggota keluarga yang menderita penyakit serupa?
Riwayat imunisasi?
Pemeriksaan Fisik
Keadaan umum
Keluhan sesak napas
Apakah pasien sakit berat dan memerlukan resusitasi seperti intubasi dan ventilasi
buatan?
Apakah pasien perlu masker oksigen? (gunakan aliran oksigen terkontrol jika ada
riwayat PPOK dan pantau analisis gas darah untuk hiperkapnia)
Adakah takipnea, takikardia, demam, sianosis, anemia, atau syok?
Adakah penggunaan otot bantu pernapasan, mengi yang terdengar jelas, atau stridor?
Adakah tanda-tanda gagal jantung atau kelebihan cairan (misalnya ronki, irama
gallop, peningkatan JVP, dan oedem perifer) ?
Adakah tanda-tanda yang menunjukkan adanya infeksi (misalnya demam, sputum,
dan tanda-tanda konsolidasi) ?
Adakah tanda-tanda efusi pleura (perkusi tumpul, suara napas menurun) ?
Adakah tanda-tanda pneumotoraks (perkusi hiperesonansi, suara napas menurun) ?
Adakah tanda-tanda emboli paru (JVP meningkat, gesekan pleura) ?
Tanda-tanda distress pernapasan ? (takipnea, penggunaan otot bantu pernapasan,
takikardia, tidak mampu menyelesaikan satu kalimat karena sesak, kecemasan,
sianosis, stridor, mengantuk atau bingung)3
Keluhan batuk
Adakah tanda-tanda konsolidasi, oedem paru, jari tabuh, atau ronkhi ?3
Pemeriksaan mulut dan faring
3

Pemeriksaan fisik pada kasus ini lebih difokuskan pada pemeriksaan bagian faring.
Pemeriksaan faring pada anak dapat dilakukan setelah pemeriksaan fisik lainnya selesai
dilakukan karena pada pemeriksaan faring ini akan membutuhkan bantuan orangtua untuk
memegang dan menenangkan anaknya.
Jika pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan spatel lidah, teknik yang terbaik
adalah dengan mendorong spatel tersebut ke bawah dan sedikit menariknya ke depan (seraya
ditekan), sementara anak mengatakan “ah”. Hati-hati, jangan sampai meletakkan spatel
terlalu belakang pada lidah karena akan memicu refleks muntah. Kadang-kadang anak yang
kecil dan merasa cemas harus dipegangi; anak ini akan mengatupkan mulutnya dan
mengerutkan bibirnya. Dalam menghadapi kasus ini, spatel harus diselipkan dengan hati-hati
di antara kedua baris giginya dan kemudian menekan lidahnya. Tindakan ini memungkinkan
Anda mendorong lidah ke bawah atau memicu refleks muntah yang membuat Anda dapat
melihat sekilas keadaan faring posterior serta tonsilnya.4
Pada pemeriksaan ini, inspeksi ukuran, posisi, kesimetrisan dan penampakan tonsil.
Ukuran tonsil bervariasi cukup luas pada anak dan sering kali digolongkan dalam skala 1+
hingga 4+; angka 1+ menunjukkan adanya celah yang terlihat jelas di antara kedua tonsil dan
angka 4+ memperlihatkan bahwa kedua tonsil saling menyentuh pada garis tengah ketika
mulut dibuka lebar-lebar. Tonsil pada anak sering terlihat lebih obstruktif daripada kenyataan
yang sebenarnya.4
Lakukan pula inspeksi pada palatum molle, uvula, dan daerah faring. Perhatikan
warna serta kesimetrisannya, dan cari eksudat, pembengkakan, ulserasi, dan pembesaran
tonsil. Hasil pemeriksaan fisik daerah faring pada penderita difteria menunjukkan daerah
tenggorok berwarna merah gelap dan pada uvula, faring, serta lidah terdapat eksudat
(pseudomembran) yang berwarna kelabu. Jalan napas pada penyakit difteria dapat tersumbat
karena adanya oedem pada faring, tonsil, atau laring.4
Pemeriksaan leher (kelenjar limfe)
Lakukan inspeksi leher dengan memperhatikan kesimetrisannya dan setiap massa atau
jaringan parut yang ada. Cari pembesaran kelenjar ludah parotis atau submandibular dan
perhatikan setiap nodus limfatikus yang terlihat.
Lakukan palpasi nodus limfatikus. Gunakan permukaan ventral jari telunjuk serta jari
tengah, dan gerakkan kulit di atas jaringan yang ada di bawahnya pada setiap daerah. Pasien
4

harus berada dalam keadaan rileks dengan leher sedikit difleksikan ke depan dan jika
diperlukan, agak difleksikan ke arah sisi yang hendak diperiksa. Biasanya, pemeriksaan
kedua sisi leher dapat dilakukan dalam satu pemeriksaan. Namun, untuk memeriksa nodus
limfatikus submental, tindakan palpasi dengan tangan yang satu sementara bagian puncak
kepala pasien ditahan dengan tangan lainnya merupakan maneuver yang akan membantu
pemeriksaan ini.4
Palpasi rangkaian nodus limfatikus pada daerah servikal anterior yang lokasinya di
sebelah anterior dan superficial muskulus sternomastoideus. Kemudian, lakukan palpasi
rangkaian nodus limfatikus pada daerah servikal posterior di sepanjang muskulus trapezius
(tepi anterior) dan muskulus sternomastoideus (tepi posterior). Fleksikan leher pasien agak ke
depan kea rah sisi yang hendak diperiksa.4
Pada kasus ini, pemeriksaan difokuskan pada pemeriksaan nodus limfatikus
submandibular dan servikal karena pada difteria, kedua kelenjar limfe ini seringkali
membesar. Limfonodi yang membesar dan nyeri tekan memberi kesan adanya peradangan
oleh karena infeksi virus atau bakteri, sedangkan limfonodi yang teraba keras member kesan
adanya keganasan. Pembesaran limfonodus dapat terjadi bilateral maupun unilateral.
Pemeriksaan paru
Pemeriksaan ini lebih ditekankan pada teknik auskultasi. Jika Anda meminta anak
kecil untuk menarik napasnya dalam-dalam, seringkali anak tersebut akan menahan napas,
sehingga menyulitkan dalam melakukan auskultasi paru. Jadi, bagi anak prasekolah akan
lebih mudah untuk membiarkannya bernapas seperti biasa. Dengarkan bunyi pernapasan
dengan memperhatikan intensitasnya dan mengenali setiap variasi dari pernapasan vesikuler
yang normal. Biasanya bunyi pernapasan lebih keras pada lapang paru anterior atas.4
Pada keadaan terdapatnya obstruksi saluran napas atas, inspirasi akan memanjang dan
disertai tanda lain seperti stridor, batuk, serta ronkhi. Stridor merupakan bunyi pernapasan
yang khas pada penderita difteria. Bunyi ini seringkali terdengar lebih keras pada leher
daripada pada dinding dada. Stridor menunjukkan obstruksi parsial laring atau trachea dan
memerlukan tindakan segera.4
5

Pemeriksaan Penunjang
Kultur
Spesimen untuk biakan harus diambil dari hidung dan tenggorok dan salah satu
tempat lesi mukokutan lain. Sebagian membran harus diambil dan diserahkan bersama
eksudat di bawahnya.5 Idealnya, specimen harus diambil oleh dokter atau personel yang
terlatih. Pasien harus duduk menghadap sumber cahaya. Sambil lidah ditekan dengan spatula,
sebuah lidi kapas steril diusapkan dengan kuat pada setiap tonsil, melalui dinding belakang
faring dan semua tempat yang meradang. Hati-hati jangan sampai menyentuh lidah atau
permukaan pipi bagian dalam (bukal). Sebaiknya mengambil dua usapan dari daerah yang
sama. Usapan yang satu dapat digunakan untuk membuat sediaan apus, sedangkan usapan
yang lain dimasukkan ke dalam wadah kaca atau plastic dan dikirim ke laboratorium.
Alternative lainnya adalah menempatkan kedua usapan dalam suatu wadah dan
mengirimkannya ke laboratorium. Jika specimen tidak dapat diproses dalam 4 jam, usapan
harus dimasukkan dalam media transport (misalnya Amies atau Stuart).6
Walaupun basil difteri tumbuh baik pada agar darah biasa, pertumbuhannya lebih baik
dengan melakukan inokulasi pada salah satu atau dua media khusus:6
1. Loeffler coagulated serum atau Dorset egg medium. Walaupun tidak selektif, kedua
media tersebut menghasilkan pertumbuhan basil difteri yang berlimpah setelah
inkubasi semalaman. Lagipula morfologi selular basil ini lebih khas, yaitu batang
yang agak bengkok, terwarna tidak beraturan, pendek sampai panjang, menunjukkan
granula metakromatik, dan tersusun dalam bentuk ‘V’ atau palisade sejajar. Granula
metakromatik lebih jelas setelah diwarnai dengan biru metilen atau pulasan Albert
daripada dengan pulasan Gram.
2. Agar darah telurit yang selektif. Media ini memudahkan isolasi saat bakteri berjumlah
sedikit, misalnya pada kasus karier yang sehat. Pada media ini, koloni basil difteri
berwarna keabuan sampai hitam dan berkembang sempurna hanya setelah 48 jam.
Koloni mencurigakan, yang mengandung basil dengan morfologi coryneform pada
pulasan Gram, harus disubkultur pada lempeng agar darah untuk memeriksa
kemurniannya dan keberadaan morfologi yang ‘khas’. Harus diingat pula bahwa C.
6

diphteriae biotipe mitis, yang paling banyak ditemukan, menunjukkan zona hemolisis-
β yang jelas pada agar darah.
Suatu laporan dugaan adanya C. diphteriae seringkali dapat diberikan pada tahap ini.
Walaupun demikian, ini harus dipastikan atau disingkirkan dengan beberapa uji biokimia
sederhana dan dengan menunjukkan adanya toksigenesitas. Karena uji toksigenesitas
mensyaratkan inokulasi pada kelinci percobaan atau suatu uji toksigenik in vitro (Elek) dan
harus dilakukan di laboratorium pusat, hanya identifikasi biokimia cepat yang akan dibahas
di sini. C. diphteriae bersifat katalase positif dan nitrat positif. Urea tidak dihidrolisis. Asam
tanpa gas dihasilkan dari glukosa dan maltose, umumnya tidak dari sakarosa. Fermentasi
glukosa dapat diuji pada media Kliger. Aktivitas urease dapat ditunjukkan pada MIU dan
reduksi nitrat pada kaldu nitrat seperti pada Enterobacteriaceae. Untuk fermentasi maltose
dan sakarosa, air pepton Andrade dapat digunakan sebagai pelarut dengan konsentrasi akhir
1% untuk tiap karbohidrat. Hasil biasanya dapat dibaca setelah 24 jam, walaupun
kemungkinan perlu diinkubasi lagi semalaman. Harus ditekankan bahwa peran laboratorium
mikrobiologi adalah untuk memastikan diagnosis klinis difteri. Terapi tidak boleh ditunda
karena menunggu hasil laboratorium.6
Diagnosis klinis difteria tidak selalu mudah ditegakkan, dan oleh klinikus-klinikus
berpengalaman dinyatakan sebagai salah satu penyakit yang cenderung untuk salah
didiagnosis. Kesalahan yang sering terjadi ialah dalam membedakan difteria dengan infeksi-
infeksi lain seperti tonsillitis, faringitis streptokokal dan infeksi Vincent. Diperlukan waktu
beberapa hari bagi laboratorium mikrobiologi untuk memastikan toksigenitas kuman difteri
yang diasingkan.7
Laboratorium tidak dapat menentukan diagnosis difteri hanya berdasarkan
pemeriksaan mikroskopis saja karena strain C. diphteriae baik yang toksigenik maupun yang
nontoksigenik tidak dapat dibedakan satu dengan lainnya secara mikroskopik, lagipula
spesies Corynebacterium yang lain pun secara morfologik mungkin serupa. Oleh karena itu,
apabila pada pemeriksaan mikroskopik ditemukan kuman-kuman berbentuk khas difteri,
maka hasil presumtif yang diberikan adalah ditemukan kuman-kuman tersangka difteri. Hal
ini menunjukkan pentingnya diagnosis bakteriologik laboratorium untuk mendapatkan cara-
cara yang mudah, cepat, sederhana, dan dipercaya yang dapat membantu klinikus dalam
menegakkan diagnosisnya. Walaupun demikian, dalam kasus-kasus tersangka klinis difteri,
7

janganlah hendaknya pemeriksaan laboratorium menjadi penyebab ditundanya pengobatan
terhadap penyakit tersebut.7
Diagnosis bakteriologik harus dianggap sebagai penunjang dan bukan sebagai
pengganti diagnosis klinik. Hapusan tenggorok atau bahan pemeriksaan lainnya harus
diambil sebelum pemberian antimikroba, dan harus segera dikirim ke laboratorium.7
Shick Test
Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan ada/tidaknya antibody terhadap toksin
difteri (antitoksin). Uji ini berguna untuk mendiagnosis kasus difteri ringan dan kasus yang
mengalami kontak dengan difteri, sehingga bisa diobati dengan sempurna. Untuk
mendiagnosis difteri secara dini, tes ini tidak dianjurkan karena membutuhkan waktu untuk
membaca hasilnya.8
Reaksi Schick dilakukan dengan menyuntikkan 0,1 ml toksin difteria 1/50 M.L.D.
secara intrakutan pada lengan bagian voler. Sebagai control, dilakukan penyuntikan serupa
dengan toksin yang telah dipanaskan terlebih dahulu 60°C selama 30 menit untuk
menghilangkan aktivitas toksinnya. Reaksi positif ditandai dengan timbulnya reaksi inflamasi
setempat yang mencapai intensitas maksimum dalam 4-7 hari, untuk selanjutnya menghilang
secara perlahan-lahan. Reaksi positif menunjukkan tidak adanya imunitas terhadap toksin
difteri. Reaksi negative menunjukkan bahwa kadar antitoksin dalam darah sudah lebih dari
0,03 unit/ml dan berarti bahwa orang tersebut kebal terhadap difteria. Reaksi alergi kadang-
kadang dijumpai pada orang dewasa dan anak-anak menjelang dewasa, terutama di daerah di
mana difteria bersifat endemic.7
Pemeriksaan darah
Pada perhitungan sel darah tepi, ditemukan leukositosis moderat dan trombositopenia.
Pemeriksaan enzim jantung
Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi adanya miokarditis.
Diagnosis Banding
Abses retrofaring
8

Abses retrofaring adalah kumpulan nanah yang terbentuk di ruang retrofaring.
Biasanya pada anak 3 bulan-5 tahun karena ruang retrofaring masih berisi kelenjar limfe.
Kuman penyebab infeksi biasanya merupakan campuran aerob dan anaerob. Sumber
infeksi berasal dari infeksi akut saluran napas atas yang secara langsung atau secara limfogen
menyebabkan infeksi kelenjar limfe retrofaring, trauma benda asing, atau tuberkulosis
cervikal.
Demam, leher kaku, nyeri dan sukar menelan. Posisi kepala hiperekstensi dan miring
ke arah yang sehat. Anak kecil akan menangis terus dan tidak mau makan atau minum. Dapat
timbul sesak napas, stridor, dan perubahan suara. Pada dinding belakang faring tampak
benjolan hiperemis yang teraba lunak.
Abses peritonsilar
Abses peritonsil terjadi sebagai akibat komplikasi tonsilitis akut atau infeksi yang
bersumber dari kelenjar mucus Weber di kutub atas tonsil. Biasanya kuman penyebabnya
sama dengan kuman penyebab tonsilitis. Biasanya unilateral dan lebih sering pada anak-anak
yang lebih tua dan dewasa muda.
Abses peritonsiler disebabkan oleh organisme yang bersifat aerob maupun yang
bersifat anaerob. Organisme aerob yang paling sering menyebabkan abses peritonsiler adalah
Streptococcus pyogenes (Group A Beta-hemolitik streptoccus), Staphylococcus aureus, dan
Haemophilus influenzae. Sedangkan organisme anaerob yang berperan adalah
Fusobacterium. Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, dan Peptostreptococcus spp.
Untuk kebanyakan abses peritonsiler diduga disebabkan karena kombinasi antara organisme
aerobik dan anaerobik.
Selain gejala dan tanda tonsilitis akut, terdapat juga odinofagia (nyeru menelan) yang
hebat, biasanya pada sisi yang sama juga dan nyeri telinga (otalgia), muntah (regurgitasi),
mulut berbau (foetor ex ore), banyak ludah (hipersalivasi), suara sengau (rinolalia), dan
kadang-kadang sukar membuka mulut (trismus), serta pembengkakan kelenjar submandibula
dengan nyeri tekan.
9

Bila ada nyeri di leher (neck pain) dan atau terbatasnya gerakan leher (limitation in
neck mobility), maka ini dikarenakan lymphadenopathy dan peradangan otot tengkuk
(cervical muscle inflammation).
Prosedur diagnosis dengan melakukan aspirasi jarum (needle aspiration). Tempat
aspiration dibius / dianestesi menggunakan lidocaine dengan epinephrine dan jarum besar
(berukuran 16–18) yang biasa menempel pada syringe berukuran 10cc. Aspirasi material
yang bernanah (purulent) merupakan tanda khas, dan material dapat dikirim untuk dibiakkan.
Trakeitis bakterialis
Trakeitis bakterialis merupakan infeksi akut saluran pernapasan atas, tidak melibatkan
epiglottis, tetapi seperti epiglotitis dan croup, trakeitis bakterialis mampu menyebabkan
obstruksi jalan napas yang mengancam jiwa. S. aureus adalah pathogen yang paling lazim
diisolasi. Virus parainfluenza tipe 1, Moraxella catarrhalis, dan H. influenzae terlibat pada
infeksi ini. Kebanyakan penderita berumur kurang dari 3 tahun, walaupun anak yang lebih
tua kadang-kadang telah terkena. Trakeitis bakterialis biasanya terjadi pasca infeksi virus
pernapasan yang jelas (terutama laringotrakeitis). Trakeitis mungkin merupakan komplikasi
bakteri penyakit virus, bukannya penyakit bakteri primer.
Khasnya, pada anak timbul batuk keras dan kasar, tampak sebagai bagian dari
laringotrakeobronkitis. Demam tinggi dan toksisitas dengan kegawatan pernapasan dapat
terjadi segera atau sesudah beberapa hari dari perbaikan yang tampak. Pengobatan yang biasa
digunakan untuk croup tidak efektif. Intubasi dan trakeostomi biasanya diperlukan. Patologi
utama yang tampak adalah pembengkakan mukosa yang setinggi kartilago krikoid,
dikomplikasi oleh sekresi purulen, kental banyak sekali. Pengisapan sekresi ini, walaupun
kadang-kadang memberikan pelegaan sementara, biasanya tidak cukup menghindarkan
perlunya jalan napas buatan.
Diagnosis didasarkan pada bukti adanya penyakit salauran pernapasan atas bakteri
yang meliputi leukositosis sedang dengan banyak bentuk batang, demam tinggi, dan sekresi
jalan napas purulen dan tidak adanya tanda-tanda klasik epiglotitis.
Faringitis bakterialis
10

Faringitis bakterialis paling sering disebabkan oleh Streptococcus hemolitikus grup A.
manifestasi klinis pada anak di atas umur 2 tahun mulai dengan keluhan nyeri kepala, nyeri
perut, dan muntah. Gejala-gejala ini dapat disertai dengan demam setinggi 40°C; kadang-
kadang kenaikan suhu tidak tampak selama 12 jam atau lebih. Beberapa jam setelah keluhan
awal, tenggorokan dapat menjadi nyeri, dan pada sepertiga penderita ditemukan pembesaran
tonsil, eksudasi, dan eritema faring. Parahnya nyeri faring tidak selalu sama dan dapat
bervariasi dari ringan hingga berat, sehingga anak sukar menelan. Dua pertiga penderita
hanya menderita eritema ringan, tanpa pembesaran tonsil dan tanpa eksudat. Limfadenopati
servikal anterior biasanya terjadi awal, dan limfonodi sering nyeri. Demam dapat berlanjut
selama 1-4 hari; pada kasus yang amat berat anak dapat tetap sakit selama 2 minggu.
Temuan-temuan fisik paling mungkin yang berkaitan dengan penyakit streptococcus
adalah kemerahan difus pada tonsil dan dinding penyangga tonsil dengan bintik petekie
palatum molle, dapat ditemukan adanya limfadenitis atau eksudasi folikuler, atau tidak.
Tanda-tanda ini walaupun lazim dijumpai pada faringitis bakterialis, namun tidak bersifat
diagnostic dan sering ditemukan juga pada faringitis virus. Konjungtivitis, rhinitis, batuk, dan
serak jarang terjadi pada faringitis yang terbukti disebabkan streptococcus, dan adanya dua
tau lebih tanda atau gejala ini member kesan diagnosis infeksi virus.
Biasanya anak berumur 6 bulan sampai 3 tahun menderita sakit yang paling berat.
Koriza dengan cairan (discharge) postnasal. Kemerahan faring yang difus, demam, muntah,
dan anoreksia adalah gejala awal. Selama beberapa hari biasanya demam 38 – 39,5°C yang
berlanjut secara tidak teratur selama 4 – 8 minggu, dan secara bertahap menjadi normal.
Dalam beberapa hari setelah penyakit mulai, limfonodus mulai membesar dan menjadi nyeri;
perjalanan adenopati secara khas parallel dengan perjalanan demam.
Faringitis Akut
(Acute Pharingitis) merupakan keradangan pada daerah faring yang terjadi kurang
dari 7 hari. Di masyarakat, peradangan pada daerah ini sering dikanal dengan radang
tenggorokan. Proses keradangan ini dapat disebabkan oleh berbagai mekanisme, salah
satunya disebabkan oleh infeksi mikroorganisme. Karena posisinya berada dalam jalur
11

pernafasan (hidung – paru-paru) dan jalur makanan (mulut-esofagus), maka sumber
pencemaran pada daerah faring dapat terjadi melalui dua jalur tersebut. Pada penderita yang
mengalami pilek, faringitis dapat terjadi oleh karena lendir yang mengalir ke belakang
(posterior) saluran hidung, dan jatuh ke daerah faring. Faringitis yang terjadi oleh karena
aliran lendir ke belakang sering diakibatkan oleh virus influenza (contohnya rhinovirus dan
adenovirus) ataupun H. Influenza.
Faringitis dengan gejala batuk disertai dahak kekuningan sangat sering dikaitkan dengan
sumber infeksi bakteri. Pada kasus radang tenggorokan yang sulit untuk sembuh, dan sering
muncul berulang dengan, maka patut dicurigai adanya infeksi Streptokokus. Kelompok
bakteri Streptokokus yang patut mendapatkan penanganan serius oleh karena komplikasinya
yang berbahaya adalah Streptokokus Beta-hemolitikum grup A (Group A beta-hemolitic
Streptocaccal/GAS).
Faktor lain yang dapat menyebabkan peradangan faring adalah infeksi jamur, alergi,
keganasan tumor, racun yang tertelan dan trauma (misalnya karena tulang ikan saat makan).
Diagnosis Kerja
Diagnosis kerja kasus tersebut adalah difteria yang merupakan toksikoinfeksi yang
disebabkan oleh Corynebacterium diphteriae.
Etiologi
Difteria berupa infeksi akut terutama pada saluran napas bagian atas disebabkan oleh
C. diphteriae yang toksigenik. Kadang-kadang kulit, konjungtiva, dan vulva dapat terinfeksi.
Difteria kulit lebih sering dijumpai di daerah-daerah tropic. Penyakit difteria terutama
menyerang anak-anak umur kurang dari 15 tahun yang tidak diimunisasi, terutama antara
umur 1-9 tahun, tetapi mungkin pula terdapat pada orang-orang dewasa yang tidak
divaksinasi atau pada bayi-bayi baru lahir. Pada saluran pernapasan, lesi primer umum
dijumpai dalam tenggorok/nasofaring di mana tampak terbentuknya pseudomembran
12

berwarna keabu-abuan. Pada kasus-kasus ringan, membrane ini mungkin tidak terbentuk.
Strain-strain non-toksigenik mungkin pula membentuk membrane yang khas, hal mana
menunjukkan bahwa eksotoksin agaknya bukan merupakan penyebabnya. Kuman difteri
berkembang biak pada tempat tersebut, sedangkan eksotoksin yang dihasilkan terbawa oleh
aliran darah ke jaringan tubuh lainnya dan menimbulkan hemoragik serta nekrotik pada
berbagai macam organ.7
Genus Corynebacterium meliputi banyak sekali spesies, baik yang bersifat saprofit
atau yang patogen bagi tanaman, hewan, dan manusia. C. diphteriae merupakan satu-satunya
spesies yang pathogen pada manusia. Ketiga biotip C. diphteriae adalah gravis, mitis, dan
intermedius. Nama-nama ini diberikan berdasarkan beratnya penyakit yang ditimbulkannya.
Gravis berarti berat/parah, mitis berarti lunak/ringan, dan intermedius berarti menengah. Kini
nama-nama ini sudah tidak sesuai lagi mengingat terdapatnya strain-strain baik yang
toksigenik maupun yang tidak pada ketiga biotip tersebut, tetapi nama-nama ini masih tetap
dipergunakan karena penting dalam identifikasi seperti dalam morfologi koloni, morfologi
sel, serta sifat-sifat biokimiawi yang berguna dalam epidemiologi.7
Kuman difteri berbentuk batang ramping berukuran 1,5-5 µm dan biasanya salah satu
ujungnya menggembung, sehingga berbentuk gada, tidak berspora, tidak bergerak, positif
Gram, dan tidak tahan asam. Di dalam preparat sering tampak membentuk susunan huruf V,
L, Y, tulisan cina atau anyaman pagar (palisade). Bentuk-bentuk pleomorfik sering dijumpai
terutama bila kuman dibiakkan dalam perbenihan suboptimal. Granula metakromatik Babes-
Ernst dapat dilihat dengan pewarnaan menurut Neisser atau biru metilen Loeffler.
Pemeriksaan terhadap granula metakromatik ini tidak spesifik.7
Meskipun C. diphteriae bersifat anaerob fakultatif, pertumbuhan optimal diperoleh
dalam suasana aerob. Untuk mengasingkan dan produksi toksin kuman, diperlukan
perbenihan-perbenihan kompleks. Untuk membiakkan kuman ini dapat dipergunakan
perbenihan Pai, perbenihan serum Loeffler, atau perbenihan agar darah. Pada perbenihan
serum, kuman ini tumbuh dengan membentuk koloni-koloni kecil mengkilap berwarna putih
keabu-abuan setelah pengeraman selama 12-24 jam pada 37°C. Perbenihan serum Loeffler ini
juga berguna karena perbenihan ini tidak menunjang pertumbuhan Streptokokus dan
Pneumokokus yang mungkin terdapat di dalam bahan pemeriksaan.7
Penambahan garam-garam telurit ke dalam perbenihan seperti perbenihan agar darah
telurit dan perbenihan McLeod, akan mengurangi jumlah pencemaran pada waktu
13

pengasingan, dan juga menyebabkan koloni-koloni kuman difteri berwarna hitam/hitam
kelabu. Sifat-sifat ini dapat dipakai untuk membantu diferensiasi ketiga biotip kuman difteri
tersebut. Pada perbenihan-perbenihan ini, tipe mitis bersifat hemolitik, sedangkan tipe-tipe
gravis dan intermedius tidak. Dalam perbenihan kaldu, tipe gravis cenderung untuk
membentuk selaput (pellicle) pada permukaan perbenihan, tipe mitis tumbuh merata (difus),
sedangkan tipe intermedius akan membentuk suatu endapan (sedimen). Asam tanpa gas
dibentuk dari berbagai karbohidrat.7
Dibandingkan dengan kuman-kuman lain yang tak berspora, C. diphteriae lebih tahan
terhadap pengaruh cahaya, pengeringan, dan pembekuan. Dalam pseudomembran kering,
tahan selama 14 hari, tetapi dalam air mendidih hanya tahan selama 1 menit, dan pada 58°C
tahan selama 10 menit. Kuman ini mudah dimatikan oleh desinfektan.7
Secara imunologik, semua toksin difteri adalah identik, tetapi kumannya sendiri
secara antigenic merupakan spesies heterogen. Ketiga tipe (gravis, mitis, intermedius)
menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan pada permukaan sel kuman. Perbedaan dalam
komponen-komponen permukaan sel dapat juga diketahui dengan bacteriophaga typing dan
pembentukan bakteriosin.7
Antigen yang erat kaitannya dengan spesifisitas tipe dari strain-strain C. diphteriae
adalah antigen K yang berupa protein termolabil dan terdapat pada permukaan dinding sel
kuman. Antigen ini berperan penting dalam imunitas anti bakteri dan hipersensitivitas, tetapi
tidak ada hubungannya dengan imunitas anti-toksin. Antigen K bersama-sama dengan
glikolipid merupakan penentu-penentu utama dalam kemampuan invasi dan virulensi kuman
difteri. Antigen O (suatu polisakarida) yang termostabil merupakan antigen grup yang umum
dijumpai pada Corynebacteria yang bersifat parasit bagi manusia dan hewan. Selain antigen
K, kuman difteri juga memiliki cord factor berupa glikolipid yang merupakan penunjang
virulensi kuman. Aktivitas cord factor C. diphteriae ini mirip dengan cord factor yang
terdapat pada M. tuberculosis.7
Pada difteria, eksotoksin yang dihasilkan oleh C. diphteriae merupakan penentu
biokimia utama dalam pathogenesis infeksi. Toksin hanya dibentuk oleh strain-strain C.
diphteriae yang lisogenik bagi bakteriofaga yang membawa gen toks (tox gene). Meskipun
demikian, strain-strain non-toksigenik dapat dijadikan toksigenik dan lisogenik bila diinfeksi
memakai Tox + bakteriofaga yang sesuai. Toksin dihasilkan sebelum partikel-partikel faga
dibentuk, dan tidak dibentuk lagi apabila sel mengalami lisis. Pembentukan toksin secara in
14

vitro sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, terutama kadar Fe inorganic dalam
perbenihan. Strain yang dipergunakan untuk pembuatan toksin guna keperluan komersial
adalah strain Park Williams 8 yang mampu tumbuh dan membentuk toksin dalam perbenihan
yang mengandung kadar Fe yang sangat rendah.7
Toksin difteri berupa rantai tunggal polipeptida dengan berat molekul kira-kira
62.000. toksin ini terdiri dari 2 fragmen, fragmen A dan B, dengan BM masing-masing
24.000 dan 38.000. kedua fragmen ini diperlukan dalam efek toksin pada hewan dan sel-sel
biakan jaringan. Hewan berbeda-beda dalam kepekaanya terhadap toksin difteri. Toksin ini
letal bagi manusia, kelinci, marmot, dan burung dalam dosis 160 nanogram/kg BB.
Epidemiologi
Difteria terdapat di seluruh dunia dan sering terdapat dalam bentuk wabah. Imunisasi
aktif anak-anak pra sekolah sangat menurunkan kejadian penyakit ini. Penyakit ini terutama
menyerang anak-anak usia 1-9 tahun. Manusia merupakan satu-satunya hospes alam, dan
karenanya merupakan satu-satunya reservoir penting dari infeksi. Kuman – kuman difteri
menghuni saluran pernapasan bagian atas dan dari sini dapat menyebar ke orang lain melalui
droplet. Dalam klinik, luka-luka pasca bedah kadang-kadang dapat terinfeksi oleh kuman ini.
Discharge ekstra respiratorik seperti yang berasal dari ulkus pada kulit dapat juga menjadi
sumber infeksi faringeal.7
Patofisiologi
Difteri merupakan penyakit infeksi yang akut dengan masa inkubasi 1-7 hari yang
disebabkan oleh strain C. diphteriae yang toksigenik. Toksin yang dibuat pada lesi local
diabsorpsi oleh darah dan diangkut ke bagian tubuh yang lain, tetapi efek toksin yang paling
utama ialah meliputi jantung dan saraf perifer. Jalan masuk infeksi yang umum untuk C.
diphteriae adalah saluran napas bagian atas, di mana organism berkembang biak pada lapisan
superficial pada selaput lendir. C. diphteriae biasanya tetap pada lapisan superficial lesi kulit
atau mukosa pernapasan, menginduksi reaksi radang local.5 Di sana, eksotoksinnya diuraikan,
menyebabkan nekrosis pada jaringan sekitarnya. Virulensi utama organism terletak pada
15

kemampuannya menghasilkan eksotoksin polipeptida 62-KD kuat, yang menghambat sintesis
protein dan menyebabkan nekrosis jaringan local.5 Respons dari peradangan membentuk
suatu pseudomembran berwarna keabuan yang terdiri dari bakteri, sel-sel epitel yang
mengalami nekrotik, sel-sel fagosit, dan fibrin. Mula-mula membran tersebut tampak pada
tonsil atau pada bagian posterior faring dan bisa menyebar ke atas ke bagian palatum yang
lunak dan keras dan ke nasofaring, atau ke bagian bawah ke laring dan trakea. Pengambilan
specimen dari daerah yang dilapisi pseudomembran ini sukar dan menampakkan perdarahan
edema submukosa.7 Paralisis palatum dan hipofaring merupakan pengaruh toksin local awal.
Penyerapan toksin dapat menyebabkan nekrosis tubulus ginjal, trombositopenia,
miokardiopati, dan demielinasi saraf.5
Difteria laryngeal sangat berbahaya sebab kemungkinan terjadi sumbatan pada
saluran napas. Difteria kulit biasa ditemukan di daerah tropic. Di Amerika Utara, luka kulit
yang juga memberikan hasil C. diphteriae positif biasanya merupakan infeksi-infeksi
sekunder pada luka gores atau pada gigitan serangga, di mana juga mengandung
Streptococcus beta hemolyticus atau Staphylococcus aureus atau keduanya.7
Luka difteria juga terjadi pada bagian depan lubang hidung, bagian dalam hidung,
mulut, mata, telinga tengah, dan pada kasus-kasus yang jarang, pada vagina. Endokarditis
yang disebabkan oleh C. diphteriae yang toksik dan nontoksik juga sudah pernah dilaporkan.
Beberapa Corynebacteria, seperti C. pseudodiphteriticum, C. hofmannii, C. xerosis, C.
pyogenes, dan C. ulcerans, biasa disebut difteroid. Kuman ini merupakan flora normal pada
selaput mukosa saluran pernapasan, saluran kencing, dan konjungtiva, kadang-kadang bisa
juga menyebabkan penyakit. Sejumlah difteroid menyebabkan penyakit pada hewan, tetapi
jarang menyerang manusia.7
Difteroid yang anaerob (Propionibacterium acnes) biasa terdapat pada kulit yang
normal, dan sering dapat ikut berperan pada patogenitas jerawat. Beberapa Corynebacteria
bisa menjadi oportunis dan menghasilkan atau menyebabkan bakteremia disertai angka
kematian yang tinggi (C. xerosis, C. equi, C. matruchotii, dan C. pseudodiphteriticum) pada
pasien-pasien yang imunosupresif. C. minutissimum merupakan penyebab eritrasma, suatu
infeksi superficial pada daerah-daerah ketiak dan pubis.7
Status kebal seseorang merupakan penentu utama apakah penyakit akan timbul atau
tidak setelah invasi oleh kuman difteri. Imunitas terhadap difteria terutama tergantung pada
adanya antitoksin dalam tubuh. Antitoksin ini dibentuk sebagai respon terhadap infeksi baik
16

klinik maupun subklinik, atau sebagai akibat imunisasi aktif buatan. Antitoksin ini dapat
dipindahkan secara alamiah, misalnya secara transplasental dalam uterus, atau secara buatan
seperti pada transfuse. Imunisasi bayi dan anak prasekolah sangat menurunkan insiden
difteria pada anak-anak, dan juga menyebabkan menurunnya jumlah karier. Kekebalan
seseorang terhadap toksin difteria dapat diketahui dengan melakukan reaksi Schick.7
Manifestasi Klinis
Manifestasi klinis difteri tergantung pada lokasi infeksi, imunitas penderita, dan
ada/tidaknya toksin difteri yang beredar dalam sirkulasi darah. Masa inkubasi difteri
umumnya 2 – 5 hari. Kemudian pasien akan memperlihatkan keluhan-keluhan yang tidak
spesifik, seperti:8
Demam dan kadang-kadang menggigil
Kerongkongan sakit dan suara parau
Perasaan tidak enak, mual dan muntah
Sakit kepala
Rinorea, berlendir kadang-kadang bercampur darah
Teraba benjolan dan sembab pada daerah leher
Fokus infeksi primer difteri adalah tonsil atau faring pada 94%, dengan hidung dan
laring dua tempat berikutnya yang paling lazim. Sesudah sekitar masa inkubasi 2-4 hari,
terjadi tanda-tanda dan gejala-gejala radang local. Demam jarang lebih tinggi dari 39°C.
Infeksi nares anterior (lebih sering pada bayi) menyebabkan rhinitis erosif, purulen,
serosanguinis dengan pembentukan membran. Ulserasi dangkal nares luar dan bibir sebelah
dalam adalah khas.5
Pada difteri tonsil dan faring, nyeri tenggorok merupakan gejala awal yang umum,
tetapi hanya setengah penderita menderita demam, dan lebih sedikit yang menderita disfagia,
serak, malaise, atau nyeri kepala. Infeksi faring ringan disertai dengan pembentukan
membrane tonsil unilateral atau bilateral, yang meluas secara berbeda-beda mengenai uvula,
palatum molle, orofaring posterior, hipofaring, dan daerah glottis. Oedem jaringan lunak di
bawahnya dan pembesaran limfonodi dapat menyebabkan gambaran ‘bull neck’. Tingkat
perluasan local berkorelasi secara langsung dengan kelemahan yang berat, gambaran bull
neck, dan kematian karena gangguan jalan napas atau komplikasi yang diperantarai toksin.5
17

Membrane pelekat seperti kulit meluas ke posterior daerah tenggorok, relative tidak
panas, dan disfagia membantu membedakan difteri dari faringitis eksudat karena
Streptococcus pyogenes dan virus Epstein-Barr. Angina Vincent, flebitis infektif dan
thrombosis vena jugularis, serta mukositis pada penderita yang mengalami kemoterapi kanker
biasanya dibedakan oleh keadaan klinis. Infeksi laring, trakea, dan bronkus dapat merupakan
perluasan primer atau sekunder dari infeksi faring. Parau, stridor, dispnea, dan batuk radang
tenggorok (croup), merupakan kunci. Perbedaan dari epiglotis bakteri, laringotrakeitis virus
berat, dan trakeitis staphylococcus sebagian berhubungan relative kecil dengan tanda-tanda
dan gejala-gejala pada penderita dengan difteri, dan terutama pada visualisasi perlekatan
pseudomembran pada saat laringoskopi dan intubasi.5
Penderita dengan difteri laring sangat cenderung tercekik karena oedem jaringan
lunak dan penyumbatan lepas epitel pernapasan tebal dan bekuan nekrotik. Pembuatan
saluran napas buatan dan pemotongan psudomembran menyelamatkan jiwa, tetapi sering ada
komplikasi obstruktif lebih lanjut, dan komplikasi toksik sistemik tidak dapat dihindarkan. C.
diphteriae kadang-kadang menimbulkan infeksi mukokutan pada tempat-tempat lain, seperti
telinga (otitis eksterna), mata (konjungtivitis purulenta dan ulseratif), dan saluran genital
(vulvovaginitis purulenta dan ulseratif). Wujud klinis, ulserasi, pembentukan membrane, dan
perdarahan submukosa membantu membedakan difteri dari penyebab bakteri dan virus lain.5
Penatalaksanaan
Antitoksin
Antitoksin spesifik merupakan terapi utama dan harus diberikan atas dasar diagnosis
klinis, karena ia hanya menetralisasi toksin bebas. Antitoksin difteri yang sekarang ini
tersedia adalah preparat dari serum kuda. Antitoksin diberikan sekali dengan dosis empiris
didasarkan pada derajat toksisitas, tempat dan ukuran membran, serta lama sakit. Kebanyakan
pakar lebih menyukai lewat intravena, dengan infuse di atas 30-60 menit. Antitoksin mungkin
tidak bermanfaat untuk manifestasi local difteri kulit, tetapi penggunaannya hati-hati karena
dapat terjadi sekuele toksik.
18

Dasar Dosis Dosis Antitoksin (U)
Hanya lesi kulit
Penyakit faring/laring, lamanya ≤ 48 jam
Lesi nasofaring
Penyakit meluas lama ≥ 72 jam
Pembengkakan leher difus
20.000 – 40.000
20.000 – 40.000
40.000 – 60.000
80.000 – 100.000
80.000 – 100.000
Tabel 1. Pemberian Antitoksin untuk Pengobatan Difteri.5
Sebanyak 10% individu sebelumnya menderita hipersensitivitas terhadap protein
kuda, bahkan penderita yang sangat sakit pun harus diuji sebelum diinfus antitoksin. Uji
intradermal yang digunakan adalah 0,02 mL antitoksin yang dilarutkan dalam garam
fisiologis 1 : 100 atau antitoksin yang dilarutkan dalam garam fisiologis 1 : 1000 jika
individu tersebut memiliki riwayat alergi binatang atau terpajan sebelumnya oleh serum
binatang.5 Reaksi segera ditentukan sebagai indurasi dengan eritema sekitarnya sekurang-
kurangnya 3 mm lebih besar daripada uji control negative, dibaca pada 15 sampai 20 menit
dengan dosis sebagai berikut:8
0,1 ml larutan 1 : 20, subkutan (dalam cairan NaCl 0,9%)
0,1 ml larutan 1 : 10, subkutan
0,1 ml tanpa dilarutkan, subkutan
0,3 ml tanpa dilarutkan, intramuscular
0,5 ml tanpa dilarutkan, intramuscular
0,1 ml tanpa dilarutkan, intravena
Untuk mereka dengan hasil uji negative, dosis awal 0,5 mL antitoksin diencerkan
dalam 10 mL garam fisiologis atau larutan glukosa 5% diberikan selambat mungkin dengan
pengamatan 30 menit; sisanya kemudian dilarutkan 1 : 20 dan diberikan pada kecepatan tidak
melebihi 1 mL/menit.5
Antimikroba
Terapi antimikroba terindikasi untuk menghentikan produksi toksin, mengobati
infeksi yang terlokalisasi, dan mencegah penularan organism pada kontak C. diphteriae
biasanya rentan terhadap berbagai agen in vitro, termasuk penisilin, eritromisin, klindamisin,
rifampin, dan tetrasiklin. Sering ada resistensi terhadap eritromisin pada populasi yang padat
19

jika obat telah digunakan secara luas. Antimikroba yang dianjurkan hanya penisilin atau
eritromisin. Eritromisin sedikit lebih unggul daripada penisilin untuk pemberantasan
pengidap nasofaring. Terapi yang tepat adalah eritromisin yang diberikan secara oral atau
parenteral (40-50 mg/kg/24 jam; maksimum 2 g/24 jam), penisilin G Kristal aqua diberikan
secara intramuskuler atau intravena (100.000 – 150.000 U/kg/24 jam; dibagi dalam 4 dosis),
atau penisilin prokain (25.000 – 50.000 U/kg/24 jam; dibagi dua dosis) diberikan secara
intramuskuler. Terapi antibiotic bukan pengganti terapi antitoksin. Terapi diberikan selama
14 hari. Terapi diberikan selama 14 hari. Hilangnya organism harus dipantau sekurang-
kurangnya 2 biakan berturut-turut dari hidung dan tenggorokan (atau kulit) yang diambil
dengan interval 24 jam setelah selesai terapi. Pengobatan dengan eritromisin diulangi jika
hasil biakan positif.5
Terapi Lainnya
Penderita dengan difteri faring ditempatkan dalam isolasi yang ketat, dan penderita
dengan difteri kulit ditempatkan pada isolasi kontak sampai biakan yang diambil sesudah
penghentian terapi menunjukkan hasil negative. Luka kulit dibersihkan menyeluruh dengan
dengan sabun dan air. Tirah baring sangat penting pada fase akut penyakit, dengan
pengembalian aktivitas fisik berpedoman pada tingkat toksisitas dan keterlibatan jantung.
Komplikasi penyumbatan jalan napas dan aspirasi harus secara agresif dicegah pada
penderita difteria orofaring dan laring, dengan pembentukan jalan napas artificial terlebih
dahulu. Gagal jantung kongestif dan malnutrisi harus dipikirkan dan dicegah.5
Komplikasi
Kegagalan napas
Difteri pada saluran pernapasan dapat berkembang dengan cepat, sehingga dapat
menimbulkan kesulitan bernapas karena terjadi sumbatan/hambatan jalan masuknya udara.8
Sumbatan pada saluran napas terjadi karena oedem pada faring, laring, trakea, maupun
bronkus oleh adanya inflamasi pada area tersebut. Pada pemeriksaan fisik ditemukan
kesulitan bernapas, takikardi, dan pucat.
Miokardiopati toksik
20

Miokardiopati toksik terjadi pada sekitar 10-25% penderita dengan difteri dan
menyebabkan 50-60% kematian. Tanda-tanda miokarditis yang tidak kentara dapat terdeteksi
pada kebanyakan penderita, terutama pada anak yang lebih tua, tetapi risiko komplikasi yang
berarti berkorelasi secara langsung dengan luasnya dan keparahan penyakit orofaring local
eksudatif dan penundaan pemberian antitoksin.5
Bukti adanya toksisitas jantung khas terjadi pada minggu ke-2 dan ke-3 sakit ketika
penyakit faring membaik, tetapi dapat muncul secara akut seawal 1 minggu bila
berkemungkinan hasil akhirnya meninggal, atau secara tersembunyi lambat sampai sakit
minggu ke-6. Takikardi di luar proporsi demam lazim dan dapat merupakan bukti efektif
toksisitas jantung atau disfungsi system saraf autonom. Pemanjangan interval PR dan
perubahan pada gelombang ST-T pada EKG relative merupakan tanda lazim.5
Disritmia jantung tunggal atau disritmia progresif dapat terjadi, seperti blockade
jantung derajat I, II, dan III, disosiasi atrioventrikuler, dan takikardi ventrikuler. Gagal
jantung kongesti klinis mungkin mulai secara tersembunyi atau akut. Kenaikan kadar
aminotransferase aspartat serum sangat parallel dengan keparahan mionekrosis. Disritmia
berat meramalkan kematian. Penemuan histologik pada kepentingan forensic menunjukkan
sedikit mionekrosis atau difus dengan respons radang akut. Penderita yang bertahan hidup
dari disritmia berat dapat memiliki efek hantaran permanen, sedangkan yang lain,
penyembuhan dari miokardiopati toksik biasanya sempurna.5
Neuropati toksik
Secara akut atau 2-3 minggu sesudah mulai radang orofaring, sering terjadi hipestesia
dan paralisis local palatum molle. Kelemahan nervus faringeus, laringeus, dan fasialis
posterior dapat menyertai, menyebabkan suara kualitas hidung, sukar menelan, dan risiko
kematian karena aspirasi. Neuropati cranial khas terjadi pada minggu ke-5 dan menyebabkan
paralisis okulomotor dan paralisis siliaris, yang Nampak sebagai strabismus, pandangan
kabur, atau kesukaran akomodasi. Polineuropati simetris mulainya 10 hari sampai 3 bulan
sesudah infeksi orofaring dan terutama menyebabkan difisit motor dengan hilangnya reflex
tendon dalam. Kelemahan otot proksimal tungkai menyebar ke distal, dan lebih sering
kelemahan distal yang menyebar kea rah proksimal. Paralisis diafragma dapat terjadi.
Mungkin terjadi penyembuhan sempurna. Dua atau 3 minggu sesudah mulai sakit jarang ada
disfungsi pusat-pusat vasomotor yang dapat menyebabkan hipotensi atau gagal jantung.5
21

Prognosis
Prognosis untuk penderita difteri tergantung pada virulensi organism (subspecies
gravis mempunya mortalitas tertinggi), umur, status imunisasi, tempat infeksi, dan kecepatan
pemberian antitoksin. Penyumbatan mekanik karena difteri laring atau difteri bull neck dan
komplikasi miokarditis menyebabkan mortalitas karena difteria yang paling besar. Mortalitas
hampir 10% untuk difteri saluran pernapasan. Pada penyembuhan, pemberian toksoid difteri
terindikasi untuk menyempurnakan dosis imunisasi booster, karena tidak semua penderita
mengembangkan antibodi pascainfeksi.5
Pencegahan
Imunisasi aktif dengan toksoid merupakan cara pencegahan terbaik. Imunisasi
pertama dilakukan pada bayi berumur antara 2-3 bulan, biasanya berupa 2 dosis APT (alum
precipitated toxoid) dikombinasikan dengan toksoid tetanus dan vaksin pertusis, yang
diberikan dengan interval 2, 4, dan 6 bulan.7 Dosis booster diberikan usia 18 dan 24 bulan,
serta pada anak sekolah berumur 5 tahun.9-11
Imunisasi pasif dengan menggunakan antitoksin berkekuatan 1.000 - 3.000 unit dapat
diberikan kepada orang tidak kebal yang sering berhubungan dengan kuman-kuman virulen.
Oleh karena proteksi semacam ini berlangsung sebentar dan pemberian antitoksin ini dapat
menimbulkan hipersensitivitas atau timbul reaksi anafilaktik pada orang yang sebelumnya
pernah kontak dengan protein asing, maka penggunaannya harus dibatasi pada keadaan-
keadaan yang memang sangat gawat.7
Kesimpulan
Pasien didiagnosa menderita difteria tonsil faring (fausial difteria) yang disebabkan
oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae dengan ditemukannya manifestasi klinik berupa
sesak napas yang sebelumnya didahului dengan demam, batuk, dan nyeri menelan . Diagnosa
pasti ditegakkan dengan ditemukannya psudomembran dan bull neck pada pemeriksaan fisik,
serta diketahui riwayat imunisasi yang tidak lengkap melalui anamnesis.
22

Daftar Pustaka
1. Gleadle J. At a glance anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jakarta: Erlangga; 2007.2. Bickley LS, Szilagyi PG. Bates buku ajar pemeriksaan fisik & riwayat kesehatan. ed
8. Jakarta: EGC; 2009.
3. Behrman RE, Kliegman R, Arvin AM. Nelson ilmu kesehatan anak volume 2. ed 15.
Jakarta: EGC; 2000.
4. Vandepitte J, Verhaegen J, Engbaek K, Rohner P, Piot P, Heuck CC. Prosedur
laboratorium dasar untuk bakteriologi klinis. ed 2. Jakarta: EGC; 2011.
5. Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Buku ajar mikrobiologi
kedokteran. ed revisi. Tangerang: Binarupa Aksara; 2012.
6. Sudoyo AW. Buku ajar ilmu penyakit dalam jilid 3. Ed 4. Jakarta: Pusat Penerbitan
Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI; 2006.
7. Anwar Z. Imunisasi pada bayi dan anak. Jurnal Kedokteran & Kesehatan Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya 2007 Januari; 39(1):1605-7.
8. Cahyono JBSB. Vaksinasi cara ampuh cegah penyakit infeksi. Yogyakarta: Kanisius; 2010.
9. Gupte S. Panduan perawatan anak. Jakarta: Pustaka Populer Obor; 2004.
23