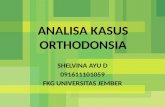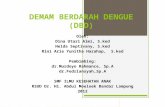Bab III Analisa Kasus
-
Upload
aprimond-syuhar -
Category
Documents
-
view
11 -
download
3
description
Transcript of Bab III Analisa Kasus

BAB III ANALISA KASUS
1. Indikasi rawat ICU
a. Sesak napas berat
Setelah 3 hari perawatan di ruang paviliun pasien mengalami sesak berat
yang ditandai dengan adanya suara napas yang berat. Telah dilakukan 3 kali
nebulizer untuk membantu melonggarkan jalan napas namun tidak ada
perbaikan, sehingga ditakukkan terjadi gagal napas akut, untuk
mengantisipasi hal tersebut pasien dibawa ke ICU agar pernapasan dapat
diawasi dengan ventilator dan jika sewaktu-waktu dibutuhkan intubasi
untuk membantu pernapasan dapat langsung dilakukan di ICU.
b. Hemoptoe
Selama perawatan pasien juga mengalami batuk yang berbuih disertai
bercak darah, hal ini menunjukkan adanya edema pulmonal pada pasien.
Keadaan ini harus segera dikoreksi dengan pemberian diuretik yang
termonitor dengan baik dengan menggunakan siring pump. Pemberian
diuretic secara intensive dapat dilakukan di ICU dengan alat dan tenaga
yang memadai.
c. Pengawasan hemodinamik
Tekanan darah yang tidak stabil pada pasien dapat memperburuk keadaan.
Sehingga dibutuhkan pengawasan keseimbangan cairan yang masuk dan
keluar, serta monitoring tanda-tanda vital yang ketat. Hal ini bertujan agar
pasien tidak jatuh kedalam fase syok. Mengingat usia pasien yang sudah tua
dan riwayat hipertensi yang tidak terkontrol, kemampuan kompensasi
jantung terhadap perubahan hemodinamik sudah menurun.

2. Diagnosis yang tepat
Saat pasien dipindahkan dari ruangan diagnose pada pasien ini adalah
HHD+CHF+post op ca kolon 2 tahun yang lalu+edema pulmonal+anemia.
Diagnose HHD ditegakkan berdasarkan anamnesa pasien memiliki riwayat
hipertensi yang tidak terkontrol serta dari pemeriksaan tanda-tanda vital
didapatkan tekanan darah 170/91 menurut JNC VII pasien ini masuk kedalam
kriteria hipertensi grade II.
Keluhan sesak napas (dispnoe) pada pasien awalnya diduga CHF diagnose ini
ditegakkan dari keluhan tersebut yang membaik jika posisi pasien didudukkan
serta posisi tidur yang memperberat keluhan (orthopnoe), selain sesak napas
pasien juga mengeluh batuk berbuih yang disertai bercak darah yang berwarna
pink dan dari pemeriksaan fisik didapatkan rhonki pada kedua lapang paru
serta pemeriksaan penunjang ro thoraks didapatkan gambaran edema pulmonal
dan kardiomegali.
Pasien juga di diagnosa kanker kolon, diagnosa ini ditegakan berdasarkan
anamnesa adanya riwayat operasi kolon 2 tahun yang lalu. Diagnosa ini
didukung dari pemeriksaan laboratorium tumor marker kolon yaitu CEA
dengan hasil 466, 11 ng/ml dengan nilai normal <5 ng/ml.
Dari hasil laboratoruim darah lengkap didapatkan Hb 7,3 gr/dl dengan nilai
normal 12-16 gr/dl. Penyebab anemia diduga akibat defisiensi nutrisi,
mengingat pasien tidak mau makan dan mual muntah sejak ±1 bulan yang lalu.
Untuk membuktikan hal tersebut dilakukan pemeriksaan lanjutan yakni sediaan
apusan darah tepi (SADT) untuk melihat morfologi sel darah pasien. Dari hasil
SADT didapatkan morfologi sel darah merah normokrom mikrositer.
Gambaran normokrom pada SDTA menunjukkan kualitas Hb normal
sedangkan gambaran mikrositer menunjukkan kualitas zat pembentuk eritrosit
menurun. Hal ini dapat dijumpai pada anemia defisinsi. Defisiensi dapat berupa
defisiensi zat besi, asam folat, vitamin B12, eritropoetin, piridoksin dan
protein.

Pada tanggal 2 Mei telah dilakukan pemeriksaan laboratorium kimia darah
untuk menilai fungsi hati dan fungsi ginjal. Dari pemeriksaan tersebut
didapatkan fungsi hati dalam batas normal, sedangkan fungsi ginjal meningkat,
hal ini dilihat dari ureum 253 mg/dl (13-44 mg/dl) dan kreatinin 9,35 mg/dl
(0,9-1,3 mg/dl). Dari nilai tersebut didapatkan laju filtrasi glomerulus (LFG)
4,5ml/1,73m2/ menit melalui formulasi sebagai berikut:
LFG= (140-usia)xBB/72xCr
= (140-72)x45/72x9,35
= 4,5ml/1,73m2/menit
Hal ini menunjukan gagal ginjal stadium akhir. Gagal ginjal pada pasien
tersebut adalah gagal ginjal kronik karena didapatkan riwayat hipertesni yang
lama dan tidak terkontrol yang menyebabkan hipoperfusi pada ginjal yang
lama kelamaan akan merusak system autoregulasi ginjal yang berakhir pada
keagagalan ginjal kronik.
Selain itu gambaran anemia juga merupakan salah satu gejala dari gagal ginjal
kronik. Anemia pada gagal ginjal kronik terjadi karena penurunan jumlah
eritropoetin yang merupakan enzim yang berperan dalam pembentukan sel
darah merah. Gambaran SADT pada gagal ginjal kronik ialah normokrom
mikrositik, hal ini sesuai dengan hasil SADT pada pasien tersebut. Sehingga
gagal ginjal kronik merupakan salah satu penyebab anemia pada pasien.
3. Tatalaksana yang tepat
Tatalaksana yang diberikan pada pasien sebagai berikut;
Hari pertama di ICU
- Oksigenasi dengan masker 6 L/ menit
- Cairan resusitasi 1000cc/24 jam
- Awasi hemodinamik
- Lasix pakai siring pump 20mg/jam
- Levofloxacine 500mg/12jam
- Digoksin, aspilet, amlodipine, spironolaktone (konsul internis)

Oksigen diberikan untuk membantu pernapasan pasien. Pasien dengan sesak
berat ditakutkan mengalami hipoksia jaringan, sehingga pemberian oksigen
harus adekuat agar tidak terjadi kerusakan jaringan.
Kebutuhan cairan per hari pada pasien dihitung berdasarkan berat badan dan
kebutuhan per jam dengan formulasi sebagai berikut:
Kebutuhan cairan per hari= 2ml/kgBB/jam
= 2ml x 45kgx 24 jam
= 2160 cc /hari
Tetapi pada pasien dengan kondisi gangguan jantung disertai edema pulmonal
kebutuhan cairan dibatasi 750-1000 cc/hari untuk meringankan beban jantung
dan tidak memperberat edema paru ataupun menambah edema di tempat lain.
Lasix merupakan golongan diuretik yang bekerja mengurangi beban kerja
jantung dengan mengurangi jumlah preload melalui sekresi air di ginjal.
Dengan demikian diharapkan dapat menurunkan tekanan darah pada pasien.
Selain itu, lasix juga berperan dalam mengeluarkan cairan pada edema paru
sehingga diharapkan edema paru berkurang dan sesak pada pasien akan
berkurang. Dosis lasix yang diberikan pada pasien adalah 20 mg/jam, dalam
satu hari pemberian lasix sebanyak 480 mg. Hal ini sesuai dengan dosis
pemberian lasix dengan dosis minimal 50 mg/ hari dan dosis maksimal 600
mg/hari.
Levofloxacine merupakan antibiotik spektrum luas. Antibiotik digunakan
untuk pengobatan infeksi pada pasien. Hal ini didukung dari hasil laboratorium
darah lengkap, yakni leukosit 18.300 /µl. Levofloxacine diberikan untuk
membunuh bakteri gram positif dan gram negative karena pada pasien tersebut
belum dilakukan pemeriksaan mikrobiologi kultur darah penyebab infeksi.
Hari kedua di ICU
- Oksigenasi dengan masker 6 L/ menit
- Cairan D5% 500cc/24 jam

- Lasix pakai siring pump 20mg/jam
- Spironolakton2 1x100mg
- Amlodipine 1x10mg
- Inf. Levofloxacine 1x500mg
- Inalapril 1x5mg
- Konsul hasil lab ureum creatinine ke dr Ronald, Sp.PD
- Pukul 16.00 wib lapor dr Ronald, SP.PD
Advice: HD cyto
- Pukul 21.00 WIB konsul dr Yusnita, Sp.An
Advice cek darah lengkap, U/C 6 jam post HD
Penggantian cairan dari ringer laktat menjadi dekstrose 5% disebabkan oleh
terjadinya peningkatan kalium dalam darah. Ringer laktat mengandung
elektrolit yang salah satunya adalah kalium ditakutkan akan meningkatkan
kadar kalium dalam darah. Sedangkan cairan dekstrose tidak mengandung
elektrolit dan bersifat hipotonis yang akan menarik cairan ke dalam intraseluler
sehingga diharapkan konsentrasi kalium di dalam darah akan menurun.
Pemberian spironolakton pada pasien kurang tepat, karena spironolaktone
merupakan golongan diuretic yang hemat kalium. Halini dapat memperberat
keadaan hiperkalemi pada pasien.
Amlodipine merupakan obat antihipertensi golongan Calsium channel blocker
(CCB) yang kerjanya menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah perifer
sehingga menurunkan resistensi perifer dan sebagai dampaknya tekanan darah
akan turun. Dosis pemberian amlodipine pada pasien sudah tepat yakni 1 x 10
mg.
Inalapril merupakan obat anti hipertensi golongan ACE-inhibitor yang kerjanya
menghambat angiotensin I converting enzyme (ACE) yakni enzim yang berperan
dalam mengubah angiotensi I menjadi angiotensin II. Dimana angiotesnin II akan
berperan dalam sekresi hormone ADH dan aldosteron yang akan menyebabkan

peningkatan jumlah cairan yang berdampak pada peningkatan teakanan darah. Hal
ini dapat dicegah dengan pemberian ACE-inhobitor.
Tindakan hemodialisa pada pasien sesuai dengan anjuran internist sudah sesuai
dengan indikasi hemodialisa. Hal ini dilihat dari jumlah LFG pada pasien yang
<15ml/1,73m2/menit yakni 4,5ml/1,73m2/menit.
Hari ketiga di ICU
- IVFD RL 1000cc/24 jam
- Levofloxacine 500mg/12jam
- Amlodipine 1x10mg
- Cek U/C
- Rencana USG abdomen
- ACC pindah ke ruangan
USG pada pasien dilakukan untuk melihat apakah terdapat massa di rongga
abdomen pasien. Pemeriksaan ini untuk menilai kanker colon yang yang
pernah dialami pasien sudah sembuh atau kanker tumbuh kembali.
Pasien dipindah keruangan karena kondisi pasien sudah stabil dan keadaan
hemodinamik pasien stabil sehingga tidak diperlukan pemantauan yang ketat
dengan monitor.