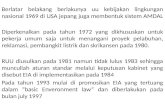AMDAL
-
Upload
ressasanover -
Category
Documents
-
view
216 -
download
1
description
Transcript of AMDAL

Pertama
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Untuk prakiraan dampak, analisis resiko lingkungan dan evaluasi dampak telah
dilakukan metode yang sangat sederhana samapai pada metode yang canggih. Prakiraan
dampak yang sederhana lebih bersifat intuitif dan sangat subyektif. Pada metode yang makin
canggih dasar ilmiah makin canggih dan dasar subyektif subyektif makin berkurang. Model
matematik, fisik serta eksperimen laboraturium dan lapangan banyak digunakan diguanakan
dalam metode yang canggih ini, namun karena pengelolaan lingkungan bersifat
antroposentris dan dengan demikian AMDAL sebagai salah satu alat pengelolaan lingkungan
yang bersifat antroposentris, alat yang canggih itupun dapat bebas dari subyektifitas.
Dalam makalah ini yang akan dibahas khusus masalah Evaluasi Dampak dan Evaluasi
Resiko, dimana evaluasi dampak ini sifatnya subyektif. Meskipun metodenya canggih,
aktifitasnya tidak dapat dieliminasi. Sementara orang menganggap, jika evaluasi itu
dilakukan secara sistematis dan pengolahan datanya dilakukan dengan komputer hasilnya
akan obyektif, itu tidak benar. Penyusunan model matematis didasarkan pada asumsi tertentu.
Bila asumsi diubah, model matematikanya pun berubah, atau paling sedikit hasil
perhitungannya, karena asumsi itu, khususnya dalam AMDAL bersifat antroposentris, di
dalam model matematis pun terkandung subyektifitas. Jika model matematis mengandung
subyektifitas itu diolah oleh komputer, subyektifitas itu tetap ada. Sebab komputer tidak
dapat berfikir sendiri, melainkan hanya dapat menjalankan perintah manusia. Namun
walupun evaluasi itu bersifat subyektif, kita harus rasional, jadi evaluasi itu kita lakukan
dengan subyektifitas rasional.
1.2 Rumusan Masalah
Dari penjelasan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana cara mengevaluasi dampak lingkungan?
2. Bagaimana cara mengevaluasi resiko dari suatu kegiatan manusia?
1.3 Tujuan
Berdasarkan permasalahan di atas, penulis dapat menyimpulkan tujuan yaitu:
1. Untuk mengetahui cara mengevaluasi dampak lingkungan dan seberapa besar nilai
dampak yang ditimbulkan.
2. Untuk mengetahui cara mengevaluasi resiko dari segala sesuatu kegiatan manusia.

1.4 Manfaat
Adapun manfaat daripada penulisan makalah ini, diharapkan dapat:
1. Dijadikan sebagai pedoman penulisan makalah mahasiswa yang lain.
2. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang evaluasi dampak dan
evaluasi resiko dalam AMDAL.
BAB II
PEMBAHASAN
EVALUASI DAMPAK DAN RESIKO
2.1 Evaluasi Dampak
Evaluasi dampak sering diartikan sebagai penilaian terhadap sesuatu perubahan yang
terjadi sebagai akibat suatu aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun
biologi.
Dampak dapat dievaluasi secara informal dan formal
A. Metode Informal
Metode Informal yang sederhana ialah dengan memberi nilai variabel, misalnya kecil,
sedang, dan besar. Cara lain ialah dengan memberi skor, misalnya dari 1 (satu) sampai 5
(lima) tanpa patokan yang jelas. Namun metode ini tidak memberi pegangan cara untuk
mendapatkan nilai penting dampak. Karena itu disinipun terjadi fluktuasi yang besar antara
anggota tim dan pemberian nilai. Kadar subyektivitas evaluasi itu tinggi. Misalnya, seorang
pejabat Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) akan cenderung
untuk memberikan nilai penting yang lebih tinggi untuk dampak margasatwa daripada
seorang pejabat Direktorat Jenderal Industri Dasar.
B. Metode Formal
Metode formal dapat dibedakan dalam:
1. Metode Pembobotan
Dalam sistem ini dampak diberi bobot dengan menggunakan metode yang ditentukan
secara eksplisit. Sebuah contoh ialah sistem pembobotan menurut Battelle utnuk
pengembangan sumberdaya air (Dee.el.al.1973). Dalam sistem Battelle ini lingkungan dibagi
dalam empat kategori utama, yaitu ekologi, fisik/ kimia, estetik, dan kepentingan manusia/
sosial. Masing-masing kategori terdiri atas komponen. Misalnya, komponen dalam katergori
ekologi ialah jenis dan populasi teresterial. Selanjutnya komponen dibagi dalam indikator
dampak. Contoh indikator dampak dalam komponen jenis dan populasi teresterial ialah

tanaman pertanian dan vegetasi alamiah. Masing-masing kategori, komponen dan indikator
dampak dinilai pentingnya relatif terhadap yang lain dengan menggunakan angka desimal
antara 0 dan 1.
Angka dalam sistem evaluasi lingkungan Battelle diragukan kegunaannya di
Indonesia, karena sistem nilai kita berbeda dengan di Amerika serikat. Namun demikian
metode untuk mendapatkan bobot dalam sistem evaluasi lingkungan itu kiranya pantas untuk
diteliti kegunaannya di Indonesia. Sudah barang tentu kategori, komponen dan indikator serta
peruntukannya harus disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Mongkol (1982) membuat
modifikasi sistem evaluasi lingkungan Battelle. Pertama fungsui nilai tidaklah dibuat dari
grafik mutu lingkungan terhadap indikator dampak, melainkan grafik mutu lingkungan
terhadap M/S, M ialah indikator dampak dan S adalah batas maksimum atau minimum
indikator dampak yang tidak boleh dilampaui.
Modifikasi kedua ialah Mongkol tidak menggunakan biaya lingkungan netto atau
manfaat lingkungan netto, melainkan nisbah manfaat/ biaya lingkungan sebagai berikut:
Nisbah manfaat/ biaya lingkungan =
Keterangan :
|Pos E| : Jumlah total dampak positif
|Neg E| : Jumlah total dampak negatif
Agar operasi matematik dapat dilakukan dalam metode pembobotan, metode itu harus
menggunakan skala interval atau skala nisbah.
2. Metode Ekonomi
Metode ini mudah diterapkan pada dampak yang mempunyai nilai uang. Untuk
dampak yang mempunyai nilai uang penerapan metode ini masih mengalami banyak
kesulitan. Cara yang umum dipakai ialah untuk memberikan harga bayangan (shadow price)
pada dampak tersebut. Harga bayangan itu didasarkan pada kesediaan orang atau pemrintah
untuk membayar / untuk menerima biaya ganti rugi untu lingkungan yang terkena dampak
tersebut. Misalnya pemerintah mengalokasikan anggaran belanja tertentu untuk penjagaan
dan pemeliharaan cagar alam dan taman nasional. Demikian pula orang bersedia untuk
mengeluarkan biaya untuk mengunjungi suatu cagar alam atau taman nasional. Besarnya
anggaran belanja atau biaya perjalanan tersebut merupakan harga bayangan cagar alam, yaitu
nilai yang diberikan oleh pemerintah/ orang kepada cagar alam itu.

Dalam hal lingkungan yang tercemar biaya deperlukan untuk membersihkan
lingkungan dari pencemaran, biaya itu makin tinggi, dengan demikian tingginya tingkat
kebersihan yang dikehendaki masyarakat.
Pada prinsifnya dampak pada manusia dapat pula diberi harga bayangan. Misalnya,
harga bayangan untuk dampak kesehatan dapat dihitung berdasarkan upah yang hilang dan
atau biaya pengobatan. Demikian pula biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk dampak
kesehatan dapat dihitung berdasarkan upah yang hilang dan atau biaya pengobatan. Demikian
pula biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pelayanan kesehatan, misalnya vaksinasi,
dapat disebut pula sebagai harga membayar perlindungan jiwa dari kematian. Banyak
tantangan masih diberiklan terhadap pemberian nilai uang pada lingkungan terutama pada
jiwa dan kesehatan manusia, tantangan itu terutama berkaitan dengan masalah etik.
2.2 Evaluasi Resiko
Seperti halnya dampak, evaluasi resiko juga bersifat subyektif. Evaluasi itu sngat dipengaruhi
oleh persepsi orang terhadap resiko. Menurut Whyte dan Burton (1982) resikok dapat
dinyatakan sebagai berikut:
R = Kementakan x Konsekuensi
Akan tetapi bagi masyarakat umum persepsi resiko ialah:
R = Kementakan x (Konsekuensi)p
Besarnya eksponen p dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya faktor yang
mempengaruhi kesediaan masyarakat untuk menerima resiko, responden di Amerika Serikat
menaksir- lebih (overes timate) resiko yang ditimbulkan oleh kejadian yang jarang terjadi dan
menaksir-kurang (underestimate) resiko yang ditimbulkan oleh kejadian yang banyak terjadi.
Evaluasi resiko sangatlah rumit, dua faktor utama selalu harus diingat : pertama,
adanya ketidakpastian ilmiah, dan kedua, persepsi masyarakat terhadap resiko hanyalah
sebagian saja didasarkan pada bukti ilmiah. Mengingat rumitnya evaluasi resiko para pakar
menyarankan, agar evaluasi dijalankan melalui proses negosiasi dan mediasi dengan
masyaraka (Bidwll et.al 1987: Klapp. 1987).
Negosiasi dan Mediasi yang ternyata telah dapat membuahkan hasil kesepakatan yang
memuaskan pihak-pihak berkepentingan dan menggalang pesan serta mereka di banyak
negara, kiranya perlu dipelajari kemungkinan penerapannya di Indonesia, metode ini kiranya
juga sesuai dengan pasal 22 PP 51 tahun 1993. Lagipula musyawarah merupakan tradisi yang
telah berakar dalam kehidupan masyarakat kita.
BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Evaluasi dampak dapat dilakukan dengan metode informal dan metode formal.
Metode formal terdiri atas metode pembobotan dan metode ekonomi.
Evaluasi dampak bersifat antroposentris, karena itu evaluasi dampak selalu
mengandung subyektifitas. Beberapa usaha telah dilakukan untuk mengurangi subyektifitas
dan manambah obyektifitas, misalnya dengan pemberian skala dan bobot. Untuk
mempermudah pengambilan keputusan skala dan bobot yang didapatkan dari masing-masing
dampak yang banyak jumlahnya, selanjutnya diusahakan untuk dirangkum menjadi satu atau
sejumlah kecil indeks komposit. Sedangkan untuk mengingat rumitnya evaluasi resiko para
pakar menyarankan agar evaluasi dijalankan melalui proses negosiasi dan mediasi dengan
masyarakat (Bidwell et.al.. 1987; Klapp. 1987). Karena proses ini telah dapat membuahkan
hasil kesepakatan yang memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan dan menggalang peran
serta mereka di banyak negara.
3.2 Saran
Semoga evaluasi dampak dan evaluasi resiko ini dapat dijadikan secara optimal dalam
pengambilan suatu keputusan.
DAFTAR PUSTAKA
- Soemarwoto, Otto, 1996. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Bandung: Gajah Mada
University Pres.
- Wiki media 2009. Evaluasi Dampak dan Resiko dalam AMDAL (online).
(Http//:www.google.com. diakses 23 Juni 2003).
- http://siendoexz.blogspot.com/2012/01/makalah-amdal.html

Kedua
PRAKIRAAN DAMPAK KOMPONEN GEOFISIK
September 2, 2012 · Disimpan dalam Uncategorized
1. Pendahuluan
Pembangunan pada hakekatnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya akibat dari pembangunan tersebut terjadi pengaruh perubahan lingkungan yang diluar tujuan dan saran pembangunan yang dikenal dengan dampak. Dampak lingkungan merupakan efek perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas proyek pembangunan. Dengan demikian dampak pembangunan juga sebagai perubahan lingkungan yang tidak direncanakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Dampak dapat mengenai pada komponen geofisik kimia, biotis, dan komponen sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat. Dampak lingkungan tersebut menjadi malasah karena perubahan kondisi lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan lebih luas daripada yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan yang direncanakan.
Lingkungan tidaklah statis, melainkan selalu berubah dengan waktu. Perubahan ini dapat bersifat daur, acak maupun dengan kecenderungan tertentu. Perubahan yang bersifat daur dapat berjangka pendek, musiman, dan berjangka panjang. Oleh karena itu untuk memprakirakan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu aktivitas pembangunan, perlu dipelajari bagaimana perubahan lingkungan tersebut dalam waktu yang akan datang tanpa proyek. Memprakirakan besaranya perubahan kualitas lingkungan yang mungkin akan terjadi dapat dilakukan dengan metode formal (seperti : model matematis, model fisik, model eksperimen dan model prakiraan cepat), maunpun metode non formal (seperti: pengalaman, analog, dan institusi).
1. 2. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam makalah “ Prakiraan dampak penting komponen geofisik” ini adalah:
1. Menetapkan dalam studi AMDAL cara prakiraan dampak penting baik dengan metode formal maupun non formal.
2. Menetapkan dalam studi AMDAL cara penetapan tingkat kepentingan dampak lingkungan sesuai dengan parameter penentu dampak penting Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintanh Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999
3. Fokus Bahasan
Fokus pembahasan yang akan dibicarakan dalam metode “prakiraan dampak penting komponen geofisik” dapat dikelompokkan kedalam hal-hal sebagai berikut:

1. Dampak lingkungan2. Metode prakiraan besaran dampak
3. Metode prakiraan tingkat kepentingan dampak
4. Ketidakpastian (uncertainty)
ad. 1. Dampak Lingkungan
Munculnya perubahan terhadap kondisi lingkungan yang disebabkan oleh suatu aktivtas manusia dapat terjadi pada komponen geofisik, kimia, biotis, sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat. Dalam kajian Amdal, prakirakaan dampak lingkungan dilakukan karena adanya rencana aktivitas/kegiatan manusia dalam pembangunan yang diprakirakan akan mengubah kualitas lingkungan Terjadinya dampak lingkungan akibat suatu kegiatan pada komponen lingkungan tersebut dapat berupa dampak primer, dampak sekunder, tersier dan seterusnya. Selain itu dampak lingkungan tersebut dapat berisifat permanen sepanjang masa maupun sementara. Untuk dapat melihat bahwa suatu dampak lingkungan atau suatu perubahan komponen lingkungan telah terjadi, harus mempunyai bahan pembanding sebagai acuan yang digunakan yaitu kualitas/ kondisi lingkungan sebelum ada kegiatan. Tanpa acuan tersebut tidak akan dapat diketahui seberapa besar perubahan kualitas terhadap komponen lingkungan yang telah/akan terjadi.
ad. 2. Metode Prakiraan Besaran Dampak
Ada beberapa pendapat mengenai pengertian dampak yang saling berbeda satu dengan yang lain. Clark, 1978 dalam Otto Sumarwoto, 1992 menjelaskan bahwa dampak pembangunan terhadap lingkungan merupakan perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan akan ada setelah ada pembangunan. Pakar lain yaitu Munn 1979 dalam Otto Sumarwoto, 1989 menjelaskan bahwa dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi yang diperkirakan akan ada tanpa adanya pembangunan dan yang diperkirakan akan ada dengan adanya pembangunan tersebut. Dari kedua pengertian tersebut diatas jelas bahwa pendapat Clark berpendapat sifat lingkungan adalah tetap stabil selama tidak ada kegiatan ata aktivitas manusia, sedangkan Munn berpendapat bahwa sifat kondisi lingkungan tidak stabil diwaktu mendatang meskipun tidak ada kegiatan pembangunan. Pendapat Munn adalah realistis bahwa sebagian besar sifat lingkungan memang tidak statis, melainkan dinamis. Sehingga muncullah ketidakpastian terhadap dampak-dampak yang diprakirakan akan terjadi diwaktu yang akan dating pada saat ada atau setelah ada kegiatan. Gambar 1 dan 2 menunjukkan perbedaan pengertian menetapkan besaran dampak menurut Clark dan Munn.
Berikut penjelasan dampak lingkungan yang dimaksud oleh Munn adalah selisih perubahanlingkungan yang akan datang apabila tanpa proyek (E1tp) dan kondisi parameter lingkungan yang sama diwaktu yang datang apabila dengan proyek ((E2dp):

(a) Tanpa Proyek
Kondisi Lingkungan Kondisi Lingkungan
Saat ini (Eo) yang akan datang apabila tanpa proyek (E1tp)
(b) Dengan Proyek
Kondisi Lingkungan Kondisi Lingkungan
Saat ini (Eo) yang akan datang apabila dengan proyek (E2dp)
(c) Dampak Lingkungan = E2dp- E 1tp (Munn,1979).
Namun pada kenyataan yang kebanyakan saat sekarang oleh para penyususn dokumen AMDAL gunakan adalah E2dp - Eo
Metode prakiraan dampak penting dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
1. Metode formal, meliputi: model matematis, model fisik, model eksperimen, dan model prakiraan cepat.
2. Motode non-formal seperti metode institusional, pengalaman (professional judgment), dan metode analog.
Prakiraan besaran dampak model matematis banyak digunakan dalam memprakirakan besarnya perubahan kualitas lingkungan dalam studi AMDAL , dengan menggunakan rumus- rumus matematik sesuai dengan parameter dari komponen lingkungan terkena dampak. Sedangkan pada medel non formal yang sering digunakan adalah mdel analog dan profesional judment.
Adapun tahapan dalam prakiraan besaran dan tingkat kepentingan dampak lingkungan akibat suatu kegiatan/usaha terhadap komponen lingkungan tertentu:
1. Buat/tentukan Rentang Skor Kualitas Lingkungan.2. Ukur kualitas lingkungan awal ( dlm hal iniparameter geofisik)
3. Konversi kualitas lingkungan awal ke dalam nilai skor (no.1)
4. Hitung/prakirakan kualitas lingkungan yang akan datang apabila rencana kegiatan dilaksanakan (setiap tahap secara terpisah)
5. Konversi kualitas lingkungan awal ke dalam nilai skor (no. 1)
6. Prakirakan besar dampak yakni selisih skor kualitas lingkungan antara butir no. dan butir no. 3)
7. Tentukan tingkat kepentingan dampak
Nilai prakiraan besaran dampak yang diperoleh berkisar antara 1 s/d 4, dengan kriteria besaran dampak sebagai berikut:

No Besaran Dampak (M) Kriteria
1 0Tidak ada dampak
2 1Kecil
3 2Sedang
4 3Besar
5 4Sangat Besar
ad. 3. Metode Prakiraan Tingkat Kepentingan Dampak
Prakiraan nilai besaran dampak (Magnitude = M) merupakan kegiatan sebelum dilakukannya evaluai terhdapa dampak besa dan penting dalam pengambilan keputusan apakah dampak tersebut akan dikelola dan dipantau dalam dokumen RKL dan RPL. Dalam evaluasi dampak nantinya dilakukan secara berama-sama (integrtad) antara besaran dampak dengan nilai kepentingan dampak (Importancy = I ).
Dampak besar dan penting merupakan satu kesatuan makna “dampak penting”. Hal ini berarti bahwa tidak selalu yang hanya mempunyai dampak besar saja yang bersifat penting, tetapi dampak yang kecil juga dimungkinkan bersifat penting. Tingkat kepentingan dampak dilakukan untuk setiap dampak hipotesis dengan mengacu pada kriteria penentu dampak penting sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yaitu:
1. Jumlah manusia yang terkena dampak2. Luas wilayah persebaran dampak
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
4. Banyaknya komponen lain yang akan terkena dampak
5. Sifat kumulatif dampak
6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak
Penetapan tingkat kepentingan dampak dari masing-masing faktor penentu tingkat kepentingan dampak dikelompokkan kedalam kriteria penting (P) dan tidak penting (TP).
Berikut “Pedoman Kriteria Penentuan Ukuran Penting (P) dan Tidak Penting (TP) Dampak” masing-masing parameter penentu tingkat kepentingan dampak menurut Kep. Ka. BAPEPDAL, Nomor: Kep-056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran dampak Penting, dengan usulan perubahan.
1) Jumlah manusia yang terkena dampak

Kriteria jumlah manusia terkena dampak dikatakan sebagai dampak penting (P) apabila terdapat > 25% manusia yang terkena dampak dan tidak mendapatkan manfaat dari proyek.
2) Luas wilayah persebaran dampak
Kriteria Luas wilayah persebaran dampakdikatagorikan kedalam dampak penting (P) apabila luas dampak > 0,25 kali luas wilayah studi, karena setidak-tidaknya dalam luasan 0,25 di wilayah studi pemanfaatan ruang cukup beragam sehingga dampaknya sudah mengenai banyk komponen lingkungan
3) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
Intensitas dan lamanya dampak berlangsung dikatagorikaan sebagai dampak penting (P) apabila intensitasnya sama atau lebih besar daripada ambang batas baku mutu, dan atau dampak berlangsung tidak hanya sesaat.
4) Banyaknya komponen lain yang akan terkena dampak
Banyaknya komponen lain yang akan terkena dampak dikatagorikan kedalam kriteria penting (P) apabila ada komponen lain yang terkena dampak (sekunder, tersier dst).
5) Sifat kumulatif dampak
6)
Dikatagorikan penting (P) apabila dampak yang diprakirakan terjadi akan mengalami penumpukan (terakumulasi) dalam satu ruang tertentu, dan dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan menimbulkan efek saling memperkuat.
7) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak
Dikatagorikan penting (P) apabila dampak yang diprakirakan terjadi tidak dapat pulih kembali (tidak berbalik) seperti kondisi semula, baik dipulihkan kembali oleh alam maupun dengan intervensi manusia.
Meskipun akhir dari hasil pembangunan adalah untuk kepentingan manusia, namun ke enam parameter penentu tingkat kepentingan dampak tersebut masing-masing diberi bobot sama yaitu bernilai 1. sehingga seluruh bobot parameter penentu kepentingan lingkungannya adalah 6. Apabila jumlah bobot hasil prakiraan suatu dampak lingkungan yang masuk katagori penting (∑P) berjumlah X, maka prosentase tingkat kepentingannya adalah:
Catatan:
I = tingkat kepentingan dampak
X = jumlah bobot dampak berdasarkan jumlah nilai parameter yang masuk katagori penting (∑P)

6 = jumlah bobot seluruh parameter penentu dampak penting
Hasil nilai perhitungan tersebut kemudian digunakan untuk menetapkan skor atau tingkat kepentingan dampaknya dengan menggunakan skor tingkat kepentingan dampak seperti dijasikan pada Table 1.
Tabel 1. Tingkat kepentingan dampak
No Nilai Prosentase ΣP
(%)Skor
(I)Tingkat Kepentingan Dampak10 – 201Tingkat kepentingan sangat rendah221- 402Tingkat kepentingan rendah341 – 603Tingkat kepentingan sedang461 – 804Tingkat kepentingan tinggi581 – 1005Tingkat kepentingan sangat tinggi
Dengan menggunakan criteria tingkat kepentingan tersebut pada Tabel 1 maka dapat dihitung unutk setiap penentuan tingkat kepentingan masing-masing dampak berdasarkan kan 6 kriteria terebut seperti disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Perhitungan prosentase dan kriteria tingkat kepentingan dampak
No ΣP
Nilai
Skala
Kepentingan
Tingkat Kepentingan Dampak
Perhitung-an
Prosentase ΣP
(%)
1
1

1/6*100%
16,667
1
Tingkat kepentingan sangat rendah2
2
2/6%100
33,333
2
Tingkat kepentingan rendah3
3
3/6*100
50,000
3
Tingkat kepentingan sedang4
4
4/6*100
66,667
Tingkat kepentingan tinggi5
5
5/6*100
83,333
5
Tingkat kepentingan sangat tinggi6
6
6/6*100

100,000
5
Tingkat kepentingan sangat tinggi
ad.4. Ketidakpastian Dampak
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar sifat kondisi lingkungan tidaklah stabil. Oleh karena disaat memprakirakan dampak yang diduga terjadi pada waktu mendatang harus dipertimbangkan adanya ketidakpastian (uncertainty). Untuk menjamin presisi pendugaan besaran dampak dan menanggulangi ketidakpastian ini maka perlu diketahui adanya kesesatan atau kesalahan yang berasal dari beberapa sumber ketidakpastian. Sumber kesalahan dimungkinkan dapat berasal dari salah satu sumber-sumber ketidakpastian berikut ini.
(1) Type of One Error atau Alpha Error
Tipe Alpha Error adalah tipe kesalahan yang terjadi pada saat dilakukan penarikan kesimpulan. Dari pendugaan terhadap dampak seluruh komponen lingkungan yang telah dilakukan harus disimpulkan komponen apa saja yang terkena dampak yang cukup besar.
(2) Type of Two Errors atau Betha Error
Tipe kesalahan ini terjadi pada saat menentukan hipotesis yang diajukan. Dalam pemikiran setiap pakar mengenai suatu komponen lingkungan tertentu pasti telah ada hipotesis tentang dampak yang mungkin akan timbul. Dalam memutuskan dampak yang sesuai dengan hipotesis, biasanya akan terjadi kesalahan.
(3) Type of S Error atau Subject Error
Kesalahan dalam pendugaan dampak tipe ini, disebabkan oleh karena tidak baiknya dalam menentukan unit cuplikan (unit sampel). Dengan unit cuplikan yang salah maka data dan informasi tentang kondisi lingkungan dan deskripsi tentang rona lingkungan juga salah. Akibatnya dalam pendugaan dampak, juga terjadi kesalahan.
(4) Type G Erro atau Group Error
Tipe kesalahan ini biasanya pada pendugaan dampak sosial ekonomi. Pada hakekatnya pendapat suatu kelompok masyarakat sering berbeda dengan pendapat individu. Apabila dilaksanakan pengamatan dalam kelompok saja, kemungkinan terjadi kesalahan karena sifat-sifat individual tidak diketahui. Sementara itu apabila diamatai sifat dan persepsi individual seringkali tidak sesuai dengan persepsi berdasarkan kelompok. Oleh karena itu perlu didapatkan informasi secara kelompok dan informasi individual. Setelah data dan informasi ini dinilai telah memenuhi syarat kemudian baru dilakukan prakiraan dampak.

(5) Type of R Error atau Replication Error
Tipe kesalahan ini terjadi karena keterangan atau data diperoleh berdasarkan pada pengamatan yang ulangan cuplikannya tidak memenuhi syarat. Pada studi Amdal hal ini sering terjadi, karena metode penelitian secara ilmiah diabaikan.
Perlu dikemukakan disini bahwa dalam prakiraan dampak lingkungan bagi parameter komponen lingkungan tertentu yang mungkin terjadi diwaktu yang akan dating perlu kiranya masalah ketidakpastian mendapat perhatian dan pertimbangan,. Pada Lampiran I diberikan contoh metode Formal (matematis) dan Non Formal (Analog Dengan Kegiatan lain yang sama/mirip) untuk memprakirakan besarn dan tingkat kepentingan dampak lingkungan.)
A. CONTOH PRAKIRAAN DAMPAK DENGAN PENDEKATAN FORMAL (Matematis)
I. Erosi Tanah
1. Prakiraan Besaran dampak
a. Eo (Rona lingkungan awal)
Besarnya erosi tanah dihitung dengan persamaan umum kehilangan tanah dari menurut Wischmeir dan Smith (1978) yang dikenal dengan USLE sebagai berikut:
A = R.K.LS.C.P
Catatan :
A : besar tanah yang hilang (ton/ha/tahun)
R : faktor erosivitas hujan
K : indeks faktor erodibilitas tanah
L : indeks faktor panjang lereng
S : indeks faktor kemiringan lereng
C : indeks faktor penutup tanaman
P : indeks faktor pengelolaan lahan
Besarnya erosivitas hujan dihitung dengan:
R (= EI30) = 2,21* P1,36
Keterangan : R = erosivitas hujan rata rata bulanan (ton/ha)

P = curah hujan bulanan rata-rata (cm)
Dengan demikian:
Curah hujan rata-rata bulanan dapat dihitung sebagai berikut:
P rata-rata tahunan = 1.656 mm/tahun
P rata-rata bulanan = 1.656 /12
= 138 mm/bulan
= 13,8 cm/jam
R (= EI30) = 2,21 x P1,36
= 2,21 x (13,8)1,36
= 78,4563 ton/ha
Indeks Faktor Erodibilitas Tanah (K)
Indeks faktor erodibilitas dihitung dengan memperhatikan karakteristik tanah dengan rumur :
2,713 M1,14 (10)-4 (12-a) + 3,25 (b-2) + 2,5 (c-2)
K = —————————————————————
100
Catatan :
Tekstur tanah daerah penelitian adalah lempung berdebu, maka nilai M = 6.330
Persentase bahan organik (C-organik) = 7,16%
Nilai a = 7,16% x 1,724
= 12,34% = 0,1234
Struktur tanah baik grumusol dan aluvium adalah gumpal, maka nilai (b) = 4
Permeabilitas tanah rata-rata daerah penelitian termasuk lambat, maka nilai (c) =4
Dengan memasukkan nilai M, a, b dan c ke dalam persamaan, nilai K dapat dihitung.
2,713 M1,14 (10)-4 (12-a) + 3,25 (b-2) + 2,5 (c-2)
K = —————————————————————

100
2,713 x 63301,14 (10)-4 (12-0,1234) + 3,25 (4-2) + 2,5 (4-2)
K = ————————————————————————–
100
80,96
K = ——-
100
= 0,8096
Faktor Besar dan Panjang Lereng
Besar lereng bervariasi antara 0 – 8%, maka LS = 0,25
Faktor tanaman penutup (penggunaan lahan)
Tanaman penutup berupa padi dan jagung secara bergantian (dominan padi, jagung, kacang tanah), maka C = 0,347.
Faktor pengelolaan lahan (P)
Sistem pengelolaan lahan baik (jagung, kacang tanah, kacasng hijau + mulsa), maka nilai P = 0,014.
Berdasarkan data tersebut, maka besarnya tanah yang hilang akibat erosi pada kondisi rona awal adalah :
A = R.K.LS.C.P
= 78,4563 x 0,8096 x 0,25 x 0,347 x 0,0,014
= 0,077/ha/tahun
Berdasarkan pada Kriteria Kualitas Lingkungan (Lampiran 2), dimana rata-rata kedalaman tanah daerah penelitian antara 30-60 cm, maka kualitas lingkungan dari parameter erosi dikatagorikan kedalam kriteria kualitas sangat baik (bobot 5)
b. E2dp (Kualitas lingkungan dengan proyek)
Dengan dibukanya area rencana pemboran sumur baru, kondisi tanah menjadi terbuka tanpa penutup lahan, sehingga berpengaruh terhadap besarnya nilai C yaitu menjadi 0,89, dan dengan tanpa konservasi tanah nilai P = 0,9. Dengan menggunakan rumus yang sama (USLE):

A = R.K.L.S.C.P
= 78,4563 x 0,8096 x 0,25 x 0,89 x 0,267
= 12,71952 ton/ha/tahun
Besarnya erosi meningkat menjadi 12, 71952 ton/ha/tahun berarti lebih besar daripada kondisi erosi rona awal. Apabila diekivalenkan dengan kriteria kualitas lingkungan pada Lampiran 2, maka kualitas lingkungan parameter erosi masuk kriteria kualitas sedang (bobot 3) Dengan demikian, pengaruh pembukaan lahan mempunyai besaran dampak negatif sedang (dampak -2).
Tabel 3. Prakiraan tingkat kepentingan dampak
No
Jenis DampakParameter Penentu Tingkat Kepentingan Dampak∑P
Kriteria Tingkat Kepentingan Dampak
Jumlah Manusia terkena dampakLuas persebaran dampak Intensitas dan lamanya
dampak berlangsung
Banyaknya kom-ponen lingkungan terkena dampakSifak kumulatif dampakBerbalik dan tidak berbaliknya dampak1.Erosi tanahTPPPPTPTP3Tingkat kepentingan sedang2.- dst-
II. Limpasan Air Permukaan (Run-off)

1. Prakiraan Besaran dampak
a. Eo (Rona lingkungan awal)
Dengan menggunakan rumus rasional di bawah ini, dapat dihiutung besarnya aliran permukaan pada saat kondisi rona awal.
R = 0,0028 C.I.A
dimana : R = debit larian air permukaan (m3/detik)
C = koefisien aliran permukaan
I = intensitas hujan (mm/jam)
A = luas area/wilayah DAS (ha)
Dari data hasil survei dan perhitungan dihasilkan:
Tanaman dominan: padi sawah + jagung (C) = 0,38 Curah hujan rata-rata 1656 mm/tahun ( I) = 0,192 mm/jam
Luas daerah (lokasi sumur dan CPP) (A) = 39 ha
R = 0,0028 x C x I x A
R = 0,028 x 0,38 x 0,192 x 39
= 0,0797 m3/dt
Berdasarkan pada Kriteria Kualitas Lingkungan (Lampiran 2), maka kualitas lingkungan dari parameter besarnya limpasan air permukaan masuk kedalam katagori kriteria kualitas baik (bobot 4)
b. Edp (Kualitas lingkungan dengan proyek)
Dengan dilakukannya pembukaan lahan yang berarti tidak ada penutupan lahan maka akan mengubah nilai koefisien run-off menjadi 0,9. Dengan rumus yang sama kuantitas aliran permukaan yang diwakili oleh debit run-off akan menjadi:
R = 0,028 C.I.A

Lahan terbuka (C) = 0,9 Curah hujan rata-rata 1656 mm/tahun ( I) = 0,192 mm/jam
Luas rencana tapak lokasi pemboran (A) = 39 Ha
R = 0,028 x C x I x A
R = 0,028 x 0,9 x 0,192 x 39
= 0.188698 m3/dt
Besarnya limpasan air permukaan meningkat menjadi 0,188698 m3/dt berarti lebih besar daripada kondisi besarnya limpasan air permukaan pada rona awal. Apabila diekivalenkan dengan kriteria kualitas lingkungan pada Lampiran 2, maka kualitas lingkungan parameter limpasan air permukaan masuk kriteria kualitas sedang (bobot 3) Dengan demikian, pengaruh pembukaan lahan mempunyai besaran dampak negatif kecil (dampak -1).
Tabel 4. Prakiraan tingkat kepentingan dampak
No
Jenis DampakParameter Penentu Tingkat Kepentingan Dampak∑P
Kriteria Tingkat Kepentingan Dampak
Jumlah Manusia terkena dampakLuas persebaran dampak Intensitas dan lamanya
dampak berlangsung
Banyaknya kom-ponen lingkungan terkena dampakSifak kumulatif dampakBerbalik dan tidak berbaliknya dampak1.Erosi tanahTPPPPTPTP3Tingkat kepentingan sedang2.- dst-
B. CONTOH PRAKIRAAN DAMPAK DENGAN PENDEKATAN NON FORMAL (Analog)
I. Peningkatan suhu udara
1. Prakiraan besaran dampak
a. Eo (Kualitas rona lingkungan awal)
Pada saat belum dilakukan pembukaan lahan, lahan masih tertutupo dengan jenis tanaman perdu yang rapat sehingga dengan dilakukan pengukuran temperatur udara didaeah tersebut, temperatur sebesar adalah 270 C. Dengan menggunakan Kreiteria Kualitas Lingkungan

(Lampiran 2) maka besarnya nilai temperatur tersebut diekivalenkan dengan kualitas lingkungan sangat baik (Skor 5)
b. E2dp (Kualitas lingkungan setelah ada proyek)
Setelah lahan dibuka dari vegtasi penutup, lahan menjadi terbuka dan langsung sinar matahari dapat mencpai permukaan tanah, sehingga dengn analog pada kegiatn lain yang serupa, temperatur pada lahan yang telah terbuka tersebut menjadi 34oC. Dengan menggunakan Kreiteria Kualitas Lingkungan (Lampiran 2) maka besarnya nilai temperatur tersebut diekivalenkan dengan kualitas lingkungan buruk (skor 2)
Nilai temperatur sebelum dilakukan pembukaan laahn adalah 27oC tetapi setelah dilakukan pembukaan lahan meningkat menjadi 34ºC Apabila diekivalenkan dengan kriteria kualitas lingkungan pada Lampiran 2, maka kualitas lingkungan parameter limpasan air permukaan masuk kriteria kualitas buruk( skor 2) Dengan demikian, pengaruh pembukaan lahan mempunyai besaran dampak negatif besar (dampak -3).
Ta bel 5. Prakiraan tingkat kepentingan dampak
No
Jenis DampakParameter Penentu Tingkat Kepentingan Dampak∑P
Kriteria Tingkat Kepentingan Dampak
Jumlah Manusia terkena dampakLuas persebaran dampak Intensitas dan lamanya
dampak berlangsung
Banyaknya kom-ponen lingkungan terkena dampakSifak kumulatif dampakBerbalik dan tidak berbaliknya dampak1.Meningkatnya suhu udaraPPPPTPTP4Tingkat kepentingan tinggi2.- dst-
II. Perubahan bentuklahan
1. Prakiraan Besaran dampak
a. Eo (kualitas Rona Lingkungan awal)

Pada awalnya permukaan lahan mempunyai bentuk aslinya dengan topografi berbukit dengan kemiringan miring hingga landai. Pada kondisi tersebut terlihat ada gejala perubahan secara alami yang ringan, sehingga berdasarkan pada Lampiran 2, kualitas lingkungannya dikatagorikan kedalam kualitas baik ( skor 4).
b. E2dp
Dengan adanya kegiatan pembangunan perumahan diwilayah tersebut, harus dilakukan pemotongan permukaan lahan dan pengurugan lembah, untuk memperoleh permukaan datar sebagai tempat (pondasi) bangunan. Secara analog dengan kegiatan yang sama ditempat lain, maka terjadi akan perubahan yang besar terhadap morofologi permukaan lahan yang mencapai hampir 50 % dari wilayah studi. Dengan demikian apabila diekuivalenkan dengaKriteria Penentu Kepentingan Dampak (Lampiran 2), maka kualitas lingkungan setelah terjadi perubahan permukaan bentuklahan dikatagorikan kedalam kualitas sangat rendah (skor 1).
Dengan demikian prakiraan besaran dampak dampak yang akan terjadi terhadap perubahan bentuklahan tersebut adalah berdampak negatif besar (dampak-3)
Tabel 6. Prakiraan Tingkat kepentingan dampak
No
Jenis DampakParameter Penentu Tingkat Kepentingan Dampak∑P
Kriteria Tingkat Kepentingan Dampak
Jumlah Manusia terkena dampakLuas persebaran dampak Intensitas dan lamanya
dampak berlangsung
Banyaknya komponen lingkungan terkena dampakSifak kumulatif dampakBerbalik dan tidak berbaliknya dampak1.Perubahan bentuklahanPPPPTPP5Tingkat kepentingan sangat tinggi2.- dst-
DAFTAR PUSTAKA
‘Anonim, 1997. Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)

Anonim, 1999. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak lingkungan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838).
Anonim, 1994. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Republik Indoensia, Nomor: Kep-056 Tahun 1994, tentang Pedoman Mengenai Ukuran dampak Penting
Anonim, 2006. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor: 08 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
Arsyad, S., 1989. Konservasi Tanah dan Air, Penerbit IPB Bandung.
Canter, L.W., 1977. Environmental Impact Assesment. Ms.Graw Hill Book Company, New York.
Chafid Fandeli, 1997. Analisis Mengenai dampak Lingkungan, Gadjah Mada Penerbit Liberty, Yogyakarta.
Erickon, P.A., 1979. Environmental Impact Assessment, Principles and Application. Academic Press. New york.
Otto Sumarwoto, 1992. Analisis Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Sarwono Hardjowigeno dan Soleh Sukmana, 1995, Menentukan Tingkat Bahaya Erosi. Laporan Teknis, No.16, Versi 1,0. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Bogor.
Sutikno, 1989. Fisografi Dalam AMDAL, Bahan Kursus AMDAL B, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Universitas Gadjah.
http://geoenviron.wordpress.com/2012/09/02/prakiraan-dampak-komponen-geofisik/